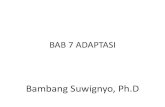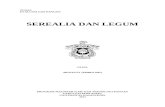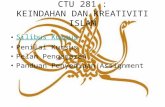Legum+%281%29
-
Upload
fitri-mey-irmawati -
Category
Documents
-
view
299 -
download
1
Transcript of Legum+%281%29
ACARA II KADAR SIANIDA DAN ASAM FITAT KORO BENGUK
A. Pendahuluan 1. Latar belakang Koro benguk (Mucuna pruriens) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang memiliki beragam varietas dan bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti kedelai. Kandungan gizi koro tidak kalah dengan kedelai yaitu karbohidratnya tinggi dan protein yang cukup tinggi serta kandungan lemak yang rendah. Akan tetapi koro juga mengandung beberapa senyawa yang merugikan yaitu glukosianida yang bersifat toksik dan asam fitat yang merupakan senyawa anti gizi. Sebaliknya, koro juga berpotensi sebagai pangan fungsional dengan adanya kandungan polifenol. Glikosida sianogenetik merupakan senyawa yang terdapat dalam bahan pangan nabati. Senyawa ini sangat beracun karena dapat terurai dan mengeluarkan hidrogen sianida (HCN). HCN cepat terserap alat pencernaan dan masuk ke dalam saluran darah. Hidrogen sianida tersebut dikeluarkan bila komoditi tersebut dihancurkan, dikunyah, mengalami pengirisan atau rusak. Asam fitat merupakan bentu utama fosfor dalam tanaman. Asam fitat sulit dicerna, sehingga fosfor dan inositol yang terdapat dalam tanaman tidak dapat digunakan oleh tubuh. Masalahgizi yang timbul karena kemampuannya mengikat mineral, terutama Ca, Mg, Fe dan Zn sehingga ketersediannya dalam tubuh menurun. Akibatnya, kecepatan hidrolisis protein oleh enzim proteolitik akan terpengaruh. 2. Tujuan Praktikum Tujuan praktikum Acara II Kadar Sianida dan Asam Fitat Koro Benguk ini adalah untuk mengetahui besarnya kadar sianida dan asam fitat pada koro benguk secara kualitatif dengan beberapa variasi perlakuan.
B. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Bahan Tempe koro benguk dibuat dari biji koro benguk yang berukuran besar dan terlihat gemuk. Biji ini diperoleh dari polong tanaman sebangsa kacang kacangan yang tumbuh menjalar. Apabila akan diolah menjadi tempe, racun yang terdapat dalam biji koro benguk harus dihilangkan terlebih dahulu. Dibandingkan dengan tempe kedelai, pengolahan tempe benguk membutuhkan pengolahan yang lebih khusus. Pengolahan itu terutama dalam perebusan dan pencucian biji benguknya. Sebab dalam biji koro benguk terkandung semacam racun yang disebut asam biru. Biji koro benguk yang akan diolah menjadi tempe harus direbus dahulu sampai masak agar kulit bijinya mudah dibuang. Untuk menghilangkan racunnya, biji benguk yang sudah masak direndam dalam air bersih yang mengalir. Semakin deras aliran airnya, maka hasilnya akan semakin bagus. Selama perendaman, racun akan keluar dan hanyut terbawa air
(Sarwono, 2000). Pada fermentasi tempe kara benguk digunakan ragi dan terlibat pula berbagai jenis mikrobia yang dapat menghasilkan enzim fitase sehingga pemecahan fitat berlangsung sangat cepat. Keberadaan mikroorganisme pada ragi mempunyai peranan penting khususnya dalam membantu menurunkan asam fitat. Semakin lama waktu fermentasi, miselium jamur semakin tebal karena pertumbuhan ragi yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan ragi dan semakin tebalnya miselium jamur maka enzim fitase yang diproduksi semakin meningkat dengan ditunjukkan semakin menurunnya kadar asam fitat (Sudarmadji, 1975). Sutardi (1988) menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus merupakan salah satu jenis jamur yang dapat menghasilkan fitase yang dapat menghidrolisis asam fitat. Faktor faktor yang mempengaruhi kadar asam fitat adalah penyimpanan dan
perlakuan pendahuluan sebelum dikonsumsi (pencucuian, pemanasan, perebusan, perendaman). Koro benguk (Mucuna pruriens) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang memiliki beragam varietas dan bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti kedelai dalam pembuatan tempe. Kandungan gizi koro tidak kalah dengan kedelai yaitu karbohidratnya tinggi dan protein yang cukup tinggi serta kandungan lemak yang rendah. Akan tetapi koro juga mengandung beberapa senyawa yang merugikan yaitu glukosianida yang bersifat toksik dan asam fitat yang merupakan senyawa anti gizi. Sebaliknya, koro juga berpotensi sebagai pangan fungsional dengan adanya kandungan polifenol. Jenis koro lokal antara lain: koro (Mucuna pruriens), koro pedang (Cannavalia ensiformis), koro glinding (Phaseolus lunatus), dan koro putih (Sudiyono, 2012). Dalam Ceballos (2012), disebutkan bahwa komposisi
mineral biji Mucuna mengandung kalium, kalsium, besi, mangan, seng, tembaga, magnesium, fosfor dan natrium dengan masing-masing 778 -1846, 104-900, 1,3-15, 0,6-9,3, 1,0-15,0, 0,3-4,3, 85-477, 98-498 dan 12,7-150,0 mg/100 g. Di antara asam amino yang ditemukan dalam biji, asam aspartat dan glutamat adalah ditemukan predominan (8,9-19 dan 8,614,4%, masing-masing), sedangkan tingkat lainnya asam amino yang ditemukan rendah (Pugalenthi et al., 2005). Biji Macuna juga mengandung faktor anti nutrisi yang banyak seperti total fenolat bebas,tanin (3,1-4,9%), L-Dopa (4,26,8%), lektin (0,31-0,71%), protease inhibitor (tripsin dan chymotrypsin), asam fitat, perut kembung faktor
(Oligosakarida), saponin (1.15-1-31%), dan hidrogen sianida (58 mg/kg) serta alkaloid (Pugalenthi et al., 2005).
2. Tinjauan Teori Banyak polongan yang dimanfaatkan sebagai makanan. Di negara yang protein hewaninya jarang dan mahal, koro memasok sejumlah besar protein di samping karbohidrat pada makanan manusia. Hampir semua polongan dapat disiapkan dirumah dengan
merendamnya dalam air, menghilangkan kulit luar dan kemudian memasaknya selama satu jam atau lebih untuk melunakkannya. Di Amerika Serikat, koro selalu diolah menjadi minyak
(Harris., Karmas, 1989) Glikosida sianogenetik merupakan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan nabati dan secara potensial sangat beracun karena dapat terurai dan mengeluarkan hidrogen sianida. Hidrogen sianida tersebut dikeluarkan bila komoditi tersebut dihancurkan, dikunyah, mengalami pengirisan atau rusak. Bila dicerna, hidrogen sianida sangat cepat terserap oleh alat pencernaan masuk ke dalam saluran darah. Tergantung jumlahnya hidrogen sianida dapat menyebabkan sakit sampai kematian (dosis mematikan 0,5 3,5 mg HCN/Kg berat badan) (Winarno, 2002). Tanaman Leguminosa merupakan tanaman penting setelah serealia. Manusia telah memanfaatkan tanaman leguminosa baik sebagai sumber pangan, maupun sebagai makanan ternak, pupuk hijau dan penahan erosi. Banyak di antara tanaman leguminosa yang dapat dimakan mempunyai kadar protein cukup tinggi dalam bijinya, tetapi masih kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan adanya kandungan glukosida HCN (Wedhastri, 1983). Karena kandungan protein tersebut koro benguk dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tepung koro sebagai substitusi suatu produk. Produk yang dihasilkan nantinya diharapkan mempunyai tambahan nilai gizi yaitu nilai protein dari tepung koro tersebut (Handajani dkk, 2010). Mucuna pruriens termasuk dalam keluarga polongan
Fabaceace, genus Mucuna dan spesies pruriens. Keluarga kacang-
kacangan (Fabaceae) merupakan yang terbesar ketiga di antara tanaman berbunga yang terdiri dari sekitar 650 marga dan 20.000 spesies. Mucuna prureins telah dilaporkan mengandung inhibitor tripsin, fitat, glikosida sianogen, tanin dan L-3,4-
dihydroxyphenylalanine (L-DOPA). Namun, konsentrasi racun dan anti-hara dalam tanaman yang diketahui dipengaruhi oleh kondisi iklim dan ekologi. Di Nigeria, Mucuna pruriens benih telah menarik perhatian namun sedikit sebagai potensi sumber protein dan energi (Nwaoguikpe et al, 2011). Biji mentah Mucuna Pruriens (koro benguk) mempunyai kadar protein 28 32%,pati 40 44% dan lemak 3 4%. Di samping kandungan bahan tadi, benguk juga mengandung asam fitat dan HCN yang cukup tinggi. Kandungan HCN dalam biji 1,66 2,00 mg/100gr, endosperm 1,78 2,30 mg/100gr dan lembaga 10,3 12,5 mg/100gr. Hal inilah yang menjadi masalah dalam penggunaan biji benguk sebagai bahan makanan selama ini. Koro benguk dapa digunakan sebagai bahan makanan olahan setelah dibebaskan dari zat racunnya (Yulinery, 1993). Senyawa glikosida hanya terdapat pada jenis kacang-kacangan tertentu khususnya koro benguk. Glikosida sianogenik dapat menyebabkan keracunan jika membebaskan asam sianida / HCN melalui reaksi hidrolisa enzimatik. Proses pengolahan seperti perendaman, pengirisan dan penghancuran menyebabkan terjadinya hidrolisis, sehingga dibebaskan senyawa HCN
(Utomo, 2004 dalam Kanetro dan Hastuti, 2006). Dalam Handajani (2010), kadar HCN koro benguk mentah ialah 14,72 mg/kg. Setelah direndam satu hari kadar tersebut turun (10,44 mg/kg), direndam dua hari (5,58 mg/kg), direndam tiga hari (3,32 mg/kg), dikukus (2,14 mg/kg), direbus (2,31 mg/kg) dan presto (1,34 mg/kg). Menurut Marniza dan Medikasari (2007), lama
perendaman di atas 48 jam dan lama perebusan 75 menit menghasilkan tempe yang memiliki karakteristik yang sesuai mutu SNI. Sebelum dilakukan analisis kandungan sianida pada sampel, dilakukan pembuatan kurva standar yang digunakan sebagai dasar untuk pembanding dalam penentuan kadar sianida dalam sampel yang menyatakan hubungan antara konsentrasi sianida dengan panjang gelombang 520 nm. Kurva ini dibuat untuk menentukan harga konsentrasi larutan sianida dengan pengukuran transmisi cahaya menggunakan spektrofotometer Vis (Kusnadi, 2001). Prinsip evaluasi kadar sianida, yaitu sampel dilarutkan pada air dan ditambahkan kloroform yang berfungsi mendestruksi HCN pada sampel. Kemudian sampel didestilasi dalam labu Kjeldahl dan HCN diserap dalam KOH 2 %. Selanjutnya ditambah alkalin pikrat dan dimasukkan dalam waterbath selama 5 menit, setelah itu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 520 nm. Alkalin pikrat berfungsi sebagai pewarna sehingga dapat dibaca absorbansinya. Asam sianida mempunyai titik didih 29C, sangat larut dalam air tetapi tidak larut dalam eter dan kloroform sehingga dipilih air sebagai pelarut asam sianida (Askurrahman, 2010).
C. Metodologi 1. Alat a. Tabung reaksi b. Spektrofotometer c. labu Kjeldahl d. Waterbath e. Timbangan analitik f. Sentrifuge g. Gelas piala 500 ml h. Pipet 5 ml
2. Bahan a. Koro benguk b. Tempe koro benguk c. Larutan HNO3 d. Larutan FeCl3 e. Amil alkohol f. Larutan amonium tiosianat g. Soda kue h. Air i. Kloroform j. Alkalin pikrat k. KOH 2%
3. Cara kerja a. Analisis Asam Fitat Siapkan 5 gram sampel koro benguk dengan berbagai perlakuan
Suspensikan dalam 50 ml larutan HNO3, diaduk selam 3 jam kemudia disaring.
0,5 ml filtrat sampel dalam tabung rekasi ditambah dengan 0,9 ml larutan HNO3 0,5 M dan larutan FeCl3
Direndam dalam penangas air 1000C selama 20 menit
Didinginkan, kemudian ditambah 5 ml amil alkohol dan 1 ml larutan ammonium thiosianat
Disentrifuse pada 1000 rpm selama 10 menit
Diamkan 12-13 menit
Lapisan amil alkohol diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada 465 nm dengan blanko amil alkohol.
b. Analisis Kadar Sianida Ditimbang 4 gr sampel koro benguk dengan berbagai perlakuan
Ditambah 125 ml air + 2,5 ml kloroform dalam labu Kjedahl
Didestilasi
HCN diserap dalam KOH 2% hingga volume total 20ml
Diambil 5ml aliquot + 5ml alkalin pikrat
Dimasukkan dalam waterbath berisi air mendidih 5 menit
Diukur absorbansi pada panjang gelombang 520 nm
D. Hasil dan Pembahasan Tabel 2.1 Data Asam Fitat Koro Benguk Kelompok Sampel 12 Koro benguk mentah 34 Koro beguk rendam 1 hari 56 Rendam air + soda kue 1 hari 78 Koro benguk rendam 3 hari 9 10 Rendam air + soda kue 3 hari 11 12 Koro benguk kukus 13 14 Koro benguk rebus 15 16 Tempe koro benguk 78 blangko Sumber: Laporan Sementara
Absorbansi 0,27 0,209 0,214 0,194 0,069 0,106 0,134 0,045
Asam fitat merupakan salah satu senyawa anti gizi yang mampu mengikat mineral, sehingga menyebabkan defisiensi mineral dalam tubuh. Asam fitat umumnya terdapat pada kacang-kacangan. Pada penentuan kadar asam fitat, mula-mula sampel koro benguk dengan berbagai variasi perlakuan disuspensikan ke dalam larutan HNO3 dan diaduk selama 3 jam kemudian disaring dan diambil filtratnya. Filtrat inilah yang akan digunakan untuk penentuan kadar asam fitat. Larutan HNO3 berfungsi sebagai pelarut yang dapat melarutkan asam fitat pada bahan. Sedangkan pengadukan selama 3 jam berfungsi untuk mengoptimalkan proses keluarnya asam fitat dari bahan. Dengan adanya pengadukan antara HNO3 dan koro benguk menyebabkan kedua bahan tersebut tercampur lebih merata, selain itu adanya pengadukan dapat menyebabkan koro benguk menjadi pecah, sehingga luas permukaan kontak dengan HNO3 menjadi lebih besar. Filtrat yang diperoleh dari perlakuan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan direaksikan dengan larutan FeCl3 dan HNO3 0,5 M. Tabung reaksi kemudian direndam dalam penangas air bersuhu 1000C selama 20 menit, setelah dingin ditambahkan amil alcohol dan ammonium thiosianat. Fe sisa akan bereaksi dengan ammonium thiosianat dan amil alcohol yang berwarna merah. Selanjutnya, sampel disentrifuse 1000 rpm selama 10 menit kemudian didiamkan selama 12-13 menit.
Setelah disentrifuse akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah berwarna merah tua. Dari hasil praktikum dapat diketahui nilai absorbansi asam fitat dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sampel koro benguk segar 0,27; koro benguk direndam + soda kue 1 hari 0,214; koro benguk direndam 1 hari 0,209; koro benguk direndam 3 hari 0,194; koro benguk rebus 0,134; koro benguk kukus 0,106; koro benguk direndam + soda kue 3 hari 0,069 dan tempe koro benguk 0,045. Nilai absorbansi menggambarkan banyaknya kandungan asam fitat pada sampel koro benguk. Dengan kandungan asam fitat yang tinggi maka semakin banyak yang bereaksi dengan FeCl membentuk Fe-fitat sehingga Fe sisa semakin kecil. Dengan demikian Fe sisa akan bereaksi dengan ammonium thiosianat dan amil alcohol yang berwarna merah Dari hasil praktikum tersebut terdapat penyimpangan dimana kadar asam fitat tempe koro benguk lebih besar dibandingkan koro benguk segar. Hal ini terjadi karena ketidaktelitian praktikan karena semakin tinggi nilai absorbansi semakin rendah kandungan asam fitat pada sampel. Koro benguk segar seharusnya memiliki nilai absorbansi sampel yang kecil sehingga kadar asam fitatnya besar. Hal ini disebabkan karena pada koro benguk segar belum mengalami proses pendahuluan/pengolahan seperti perendaman dan perebusan yang dapat menurunkan kadar asam fitat dalam bahan. Perendaman koro benguk dengan penambahan soda kue lebih efektif menurunkan kandungan asam fitat dibanding perendaman dengan air biasa. Soda kue akan mengikat asam fitat dan bereaksi membentuk garam, CO2, air, sehingga menyebabkan penurunan
kandungan asam fitat Pengukusan merupakan perlakuan yang lebih efektif dibandingkan perebusan karena uap air yang digunakan memiliki suhu diatas titik didih air yang digunakan pada saat perebusan. Dari hasil praktikum ini diketahu bahwa pemanasan juga dapat menurunkan kandungan asam fitat koro benguk. Namun keberadaan asam fitat belum sepenuhnya dapat
dihilangkan. Dengan adanya perlakuan panas, pH atau perubahan kekuatan ionik selama pengolahan dapat mengakibatkan terbentuknya garam fitat yang sukar larut. Pada fermentasi tempe kara benguk digunakan ragi dan terlibat pula berbagai jenis mikrobia yang dapat menghasilkan enzim fitase sehingga pemecahan fitat berlangsung sangat cepat. Keberadaan mikroorganisme pada ragi mempunyai peranan penting khususnya dalam membantu menurunkan asam fitat. Semakin lama waktu fermentasi, miselium jamur semakin tebal karena pertumbuhan ragi yang semakin meningkat. Dengan pertumbuhan ragi dan semakin tebalnya miselium jamur maka enzim fitase yang diproduksi semakin meningkat dengan ditunjukkan semakin menurunnya kadar asam fitat Sudarmadji (1975). Sutardi (1988) menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus merupakan salah satu jenis jamur yang dapat menghasilkan fitase yang dapat menghidrolisis asam fitat. Faktor faktor yang mempengaruhi kadar asam fitat adalah penyimpanan dan perlakuan pendahuluan sebelum dikonsumsi
(pencucuian, pemanasan, perebusan, perendaman). Tabel 2.2 Data Hasil Pengamatan Larutan Standar KCN Aquadest (ml) Asam Pikrat (ml) Absorbansi (ml) 0 5 5 0,005 0,5 4,5 5 0,214 1 4 5 0,367 1,5 3,5 5 0,583 2 3 5 0,771 2,5 2,5 5 0,854 Sumber: Laporan Sementara Y = 2,92x + 0,0276 Pembuatan kurva standar digunakan sebagai dasar untuk pembanding dalam penentuan kadar sianida dalam sampel yang menyatakan hubungan antara konsentrasi sianida dengan panjang gelombang 520 nm. Kurva ini dibuat untuk menentukan harga konsentrasi larutan sianida dengan pengukuran transmisi cahaya menggunakan spektrofotometer Vis (Kusnadi, 2001). Kurva standar digunakan untuk Mg KCN 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3
melihat nilai absorbansi, semakin tinggi konsentrasi larutan standar maka nilai absorbansi akan semakin tinggi. Tabel 2.3 Data Perhitungan Sianida Koro Benguk Kelompok Sampel Absorbansi 12 Koro benguk mentah 34 Koro beguk rendam 1 hari 56 Rendam air + soda kue 1 hari 78 Koro benguk rendam 3 hari 9 10 Rendam air + soda kue 3 hari 11 12 Koro benguk kukus 13 14 Koro benguk rebus 15 16 Tempe koro benguk Sumber: Laporan Sementara 0,102 0,080 0,132 0,297 0,025 0,282 0,169 0,306 Mg KCN 0,0254 0,0179 0,0357 0,0922 -0,00089 0,0871 0,0484 0,0953 HCN (mg/ml) 2,54x10-3 1,79x10-3 3,57x10-3 9,22x10-3 -8,9x10-5 8,71x10-3 4,84x10-3 9,53x10-3
Koro benguk (Mucuna pruriens) merupakan salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang memiliki beragam varietas dan bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti kedelai dalam pembuatan tempe. Kandungan gizi koro tidak kalah dengan kedelai yaitu karbohidratnya tinggi dan protein yang cukup tinggi serta kandungan lemak yang rendah. Akan tetapi koro juga mengandung beberapa senyawa yang merugikan yaitu glukosianida yang bersifat toksik dan asam fitat yang merupakan senyawa anti gizi. Sebaliknya, koro juga berpotensi sebagai pangan fungsional dengan adanya kandungan polifenol. Jenis koro lokal antara lain: koro (Mucuna pruriens), koro pedang (Cannavalia ensiformis), koro glinding (Phaseolus lunatus), dan koro putih (Sudiyono, 2012). Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar sianida dari sampel koro benguk mentah, koro benguk rendam 1 hari, koro benguk rendam air + soda kue 1 hari, koro benguk rendam 3 hari, koro benguk rendam air + soda kue 3 hari, koro benguk kukus, koro benguk rebus dan tempe koro benguk. Prinsip evaluasi kadar sianida, yaitu sampel dilarutkan pada air dan ditambahkan kloroform yang berfungsi mendestruksi HCN pada sampel. Kemudian sampel didestilasi dalam labu Kjeldahl dan HCN diserap dalam KOH 2 %. Selanjutnya ditambah alkalin pikrat dan dimasukkan dalam waterbath selama 5 menit, setelah itu diukur
absorbansinya pada panjang gelombang 520 nm. Alkalin pikrat berfungsi sebagai pewarna sehingga dapat dibaca absorbansinya. Asam sianida mempunyai titik didih 29C, sangat larut dalam air tetapi tidak larut dalam eter dan kloroform sehingga dipilih air sebagai pelarut asam sianida (Askurrahman, 2010). Dari hasil praktikum menunjukkan bahwa jumlah sianida dalam sampel menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada sampel koro benguk mentah kandungan sianida sebesar 2,54x10-3 mg/ml, koro benguk rendam 1 hari sebesar 1,79x10-3 mg/ml, koro benguk rendam air + soda kue 1 hari sebesar 3,57x10-3 mg/ml, koro benguk rendam 3 hari sebesar 9,22x10-3 mg/ml, koro benguk rendam air + soda kue 3 hari sebesar -8,9x10-5 mg/ml, koro benguk kukus sebesar 8,71x10-3 mg/ml, koro benguk rebus sebesar 4,84x10-3 mg/ml dan tempe koro benguk sebesar 9,53x10-3 mg/ml. Dari hasil tersebut, dapat diurutkan kandungan sianida dari masing-masing sampel dari yang terbesar ke yang terkecil sebagai berikut: tempe koro benguk > koro benguk rendam 3 hari > koro benguk kukus > koro benguk rebus > koro benguk rendam air + soda kue 1 hari > koro benguk mentah > koro benguk rendam 1 hari > koro benguk rendam air + soda kue 3 hari. Seharusnya, urutan kandungan sianida dari masing-masing sampel tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil sebagai berikut: koro benguk mentah > koro benguk rendam 1 hari > koro benguk rendam air + soda kue 1 hari > koro benguk rendam 3 hari > koro benguk rendam air + soda kue 3 hari > koro benguk kukus > koro benguk rebus > tempe koro benguk. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Utomo (2004) dalam Kanetro dan Hastuti (2006) bahwa proses pengolahan seperti perendaman, pengirisan dan penghancuran menyebabkan terjadinya hidrolisis, sehingga dibebaskan senyawa HCN. Selain itu, Handajani (2010) juga mengemukakan bahwa kadar HCN koro benguk mentah ialah 14,72 mg/kg. Setelah direndam satu hari kadar tersebut turun (10,44 mg/kg), direndam dua hari (5,58 mg/kg), direndam tiga hari (3,32 mg/kg), dikukus (2,14 mg/kg), direbus (2,31 mg/kg) dan presto (1,34 mg/kg).
E. Kesimpulan Kesimpulan yang didapat dari praktikum acara II Kadar Sianida dan Asam Fitat Koro Benguk adalah: 1. Urutan kadar asam fitat pada koro benguk dari yang tertinggi ke yang terendah adalah Koro benguk mentah > Rendam air + soda kue 1 hari > Koro beguk rendam 1 hari > Koro benguk rendam 3 hari > Koro benguk rebus > Koro benguk kukus > Rendam air + soda kue 3 hari > Tempe koro benguk. 2. Faktorfaktor yang mempengaruhi kadar asam fitat adalah
penyimpanan dan perlakuan pendahuluan sebelum dikonsumsi (pencucian, pemanasan, perebusan, perendaman). 3. Urutan kandungan sianida pada koro benguk dari yang tertinggi ke yang terendah adalah tempe koro benguk (9,53x10-3 mg/ml) > koro benguk rendam 3 hari (9,22x10-3 mg/ml) > koro benguk kukus (8,71x10-3 mg/ml) > koro benguk rebus (4,84x10-3 mg/ml) > koro benguk rendam air + soda kue 1 hari (3,57x10-3 mg/ml) > koro benguk mentah (2,54x10-3 mg/ml) > koro benguk rendam 1 hari (1,79x10-3 mg/ml) > koro benguk rendam air + soda kue 3 hari (-8,9x10-5 mg/ml). 4. Faktor yang mempengaruhi kadar HCN antara lain perendaman, pengirisan, penghancuran, perebusan, pengukusan dan fermentasi.
LAMPIRAN
Y =2,92x + 0,0276
Y = 2,92x + 0,0276 0,102 = 2,92x + 0,0276 x = 0,0254 Kadar HCN = = = 2,54x10-3( )
DAFTAR PUSTAKA
Askurrahman. 2010. Isolasi dan Karakterisasi Linamarase Hasil Isolasi dari Umbi Singkong (Manihot esculenta Crantz). Jurnal Agrointek Vol 4 No. 2. Universitas Trunojoyo. Bangkalan. Ceballos, Angel Isauro Ortiz. 2012. Velvet Bean (Mucuna pruriens var. utilis) a Cover Crop as Bioherbicide to Preserve the Environmental Services of Soil. Environmental Impact Studies and Management Approaches. Mexico. Handajani, Sri dkk. 2010 . Pengolahan Hasil Pertanian; Teknologi Tradisional dan Terkini. UNS Press. Surakarta Harris, Robert S., Karmas, Endel. 1989. Evaluasi Gizi Pada Pengolahan Bahan Pangan. ITB. Bandung. Kanetro, B dan Hastuti, S. 2006. Ragam Produk Olahan Kacang-kacangan. Universitas Wangsa Manggala. Yogyakarta. Nwaoguikpe et al. 2011. The Effects of Processing on the Proximate and Phytochemical Compositions of Mucuna pruriens Seeds (Velvet Beans). Journal of Nutrition 10 (10): 947-951, ISSN 1680-5194. Nigeria. Sarwono. 2000. Membuat Tempe dan Oncom. Penebar Swadaya. Jakarta. Sudarmadji, 1975. Certain Chemical and Nutritional Aspect of Soybean tempeh. Michigan State University. Sudiyono. 2012. Penggunaan Na2hco3 Untuk Mengurangi Kandungan Asam Sianida (HCN) Koro Benguk Pada Pembuatan Koro Benguk Goreng. Universitas Widyagama Malang. Sutardi, 1988. Phytase Activity During Tempe Production. Dept of Food Science and Technology. The university Of New South Wales. Wedhastri, Sri dkk. 1983. Pemanfaatan Biji Kecipir Sebagai Sumber Protein Dalam Bentuk Tempe. Balai Pustaka. Jakarta. Winarno, FG. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Yulinery dkk. 1993. Pembuatan Koro Benguk (Mucuna pruriens) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Kecap dan Tauco. Puslitbang Biologi. LIPI.