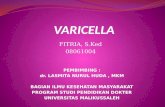Lapsus
-
Upload
nacha-malikha -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of Lapsus
BAB I
PENDAHULUAN
Anestesiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mendasari berbagai
tindakan meliputi pemberian anestesi, penjagaan keselamatan penderita yang
mengalami pembedahan, pemberian bantuan hidup dasar, pengobatan intensif
pasien gawat, terapi inhalasi dan penanggulangan nyeri menahun. Bersama-sama
cabang kedokteran lain serta anggota masyarakat ikut aktif mengelola bidang
kedokteran gawat darurat(1).
Pasien yang akan menjalani anestesi dan pembedahan (elektif atau darurat)
harus dipersiapkan dengan baik. Pada prinsipnya dalam penatalaksanaan anestesi
pada suatu operasi terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu pra
anestesi yang terdiri dari persiapan mental dan fisik pasien, perencanaan anestesi,
menentukan prognosis dan persiapan pada pada hari operasi. Tahap
penatalaksanaan anestesi yang terdiri dari premedikasi, masa anestesi dan
pemeliharaan. Serta tahap pemulihan dan perawatan pasca anestesi(1).
Apendisitis merupakan peradangan pada appendiks Bila diagnosis sudah
pasti, maka terapi yang paling tepat dengan tindakan operatif, yang disebut
apendekomi. Penundaan operasi dapat menimbulkan bahaya, antara lain abses
atau perforasi. Apendisitis akut temasuk operasi emergensi. Pada operasi
emergensi, kondisi pasien harus dipersiapkan seoptimal mungkin. Persiapannya
sama seperti operasi elektif, hanya segala sesuatunya dilakukan saat itu juga.
Operasi intra abdominal paling baik dilakukan dengan anestesia umum
endotrakeal(2).
1
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. APENDISITIS
Apendisitis merupakan peradangan pada apendiks. Apendisitis pada
awalnya dapat sembuh spontan, namun akan terjadi jaringan parut dan fibrosis.
Risiko untuk terjadinya serangan kembali adalah 50 %. Apendisitis yang parah
dapat menyebabkan apendiks pecah dan membentuk nanah di dalam rongga
abdomen atau peritonitis. Terjadinya apendisitis umumnya karena bakteri. Namun
terdapat banyak sekali faktor pencetus, di antaranya sumbatan lumen apendiks,
timbunan tinja yang keras (fekalit), makanan rendah serat, tumor apendiks, dan
pengikisan mukosa apendiks akibat parasit seperti E. hystolitica. Terdapat gejala
awal yang khas, yaitu nyeri pada perut kanan bawah, yang disebut titik
Mc.Burney. Seringkali disertai dengan rasa mual, bahkan kadang muntah.
Berbeda dengan apendisitis akut, apendisitis kronis pada palpasi didapatkan massa
atau infiltrat yang nyeri tekan dan leukosit yang sangat tinggi. Pada beberapa
keadaan, apendisitis agak sulit didiagnosis, sehingga dapat menyebabkan
terjadinya komplikasi yang lebih parah. Hal ini sering menjadi penyebab
terlambatnya diagnosis, sehingga lebih dari setengah penderita baru dapat
didiagnosis setelah perforasi. Apendiks yang pernah meradang tidak akan sembuh
sempurna, tetapi akan membentuk jaringan parut yang akan menyebabkan
perlengketan dengan jaringan sekitarnya. Perlengketan ini dapat menimbulkan
keluhan berulang di perut kanan bawah. Pada suatu saat, ketika meradang lagi,
yang disebut apendisitis eksaserbasi akut. Bila diagnosis sudah pasti, maka terapi
yang paling tepat dengan tindakan operatif, yang disebut apendektomi. Penundaan
operasi dapat menimbulkan bahaya, antara lain abses atau perforasi (5)
B. ANESTESI REGIONAL (SPINAL)
Anestesi blok subaraknoid atau biasa disebut anestesi spinal adalah
tindakan anestesi dengan memasukan obat analgetik ke dalam ruang subaraknoid
2
di daerah vertebra lumbalis yang kemudian akan terjadi hambatan rangsang
sensoris mulai dari vertebra thorakal 4.(1)(3)
II. 2. INDIKASI
Untuk pembedahan,daerah tubuh yang dipersyarafi cabang T4 kebawah
(daerah papila mamae kebawah ). Dengan durasi operasi yang tidak terlalu lama,
maksimal 2-3 jam. [1][3]
II.3. KONTRA INDIKASI
Kontra indikasi pada teknik anestesi subaraknoid blok terbagi menjadi dua
yaitu kontra indikasi absolut dan relatif.
Kontra indikasi absolut :
Infeksi pada tempat suntikan. : Infeksi pada sekitar tempat suntikan
bisa menyebabkan penyebaran kuman ke dalam rongga subdural.
Hipovolemia berat karena dehidrasi, perdarahan, muntah ataupun
diare. : Karena pada anestesi spinal bisa memicu terjadinya
hipovolemia.
Koagulapatia atau mendapat terapi koagulan.
Tekanan intrakranial meningkat. : dengan memasukkan obat kedalam
rongga subaraknoid, maka bisa makin menambah tinggi tekanan
intracranial, dan bisa menimbulkan komplikasi neurologis
Fasilitas resusitasi dan obat-obatan yang minim : pada anestesi spinal
bisa terjadi komplikasi seperti blok total, reaksi alergi dan lain-lain,
maka harus dipersiapkan fasilitas dan obat emergensi lainnya
Kurang pengalaman tanpa didampingi konsulen anestesi. : Hal ini
dapat menyebabkan kesalahan seperti misalnya cedera pada medulla
spinalis, keterampilan dokter anestesi sangat penting.
Pasien menolak.
Kontra indikasi relatif :
Infeksi sistemik : jika terjadi infeksi sistemik, perlu diperhatikan
apakah diperlukan pemberian antibiotic. Perlu dipikirkan
kemungkinan penyebaran infeksi.
3
Infeksi sekitar tempat suntikan : bila ada infeksi di sekitar tempat
suntikan bisa dipilih lokasi yang lebih kranial atau lebih kaudal.
Kelainan neurologis : perlu dinilai kelainan neurologis sebelumnya
agar tidak membingungkan antara efek anestesi dan deficit neurologis
yang sudah ada pada pasien sebelumnya.
Kelainan psikis
Bedah lama : Masa kerja obat anestesi local adalah kurang lebih 90-120
menit, bisa ditambah dengan memberi adjuvant dan durasi bisa bertahan
hingga 150 menit.
Penyakit jantung : perlu dipertimbangkan jika terjadi komplikasi kea rah
jantung akibat efek obat anestesi local.
Hipovolemia ringan : sesuai prinsip obat anestesi, memantau terjadinya
hipovolemia bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan atau cairan
Nyeri punggung kronik : kemungkinan pasien akan sulit saat diposisikan.
Hal ini berakibat sulitnya proses penusukan dan apabila dilakukan berulang-
ulang, dapat membuat pasien tidak nyaman [1][3]
II. 4. STRUKTUR ANATOMI VERTEBRA
Gambar 1 : Kolumna Vertebralis [4]
Tulang vertebra terdri dari 33 tulang: 7 buah tulang servikal, 12 buah
tulang torakal, 5 buah tulang lumbal, 5 buah tulang sakral. Tulang servikal,
torakal dan lumbal masih tetap dibedakan sampai usia berapapun, tetapi tulang
4
sakral dan koksigeus satu sama lain menyatu membentuk dua tulang yaitu tulang
sakum dan koksigeus.
Kolumna vertebralis mempunyai lima fungsi utama, yaitu: (1) menyangga
berat kepala dan dan batang tubuh, (2) melindungi medula spinalis, (3)
memungkinkan keluarnya nervi spinalis dari kanalis spinalis, (4) tempat untuk
perlekatan otot-otot, (5) memungkinkan gerakan kepala dan batang tubuh
Tulang vertebra secara gradual dari cranial ke caudal akan membesar
sampai mencapai maksimal pada tulang sakrum kemudian mengecil
sampai apex dari tulang koksigeus. Struktur demikian dikarenakan beban yang
harus ditanggung semakin membesar dari cranial hingga caudal sampai
kemudian beban tersebut ditransmisikan menuju tulang pelvis melalui articulatio
sacroilliaca.
Korpus vertebra selain dihubungkan oleh diskus intervertebralis juga oleh
suatu persendian sinovialis yang memungkinkan fleksibilitas tulang punggung,
kendati hanya memungkinkan pergerakan yang sedikit untuk mempertahankan
stabilitas kolumna vertebralis guna melindungi struktur medula spinalis yang
berjalan di dalamnya. Stabilitas kolumna vertebralis ditentukan oleh bentuk dan
kekuatan masing-masing vertebra, diskus intervertebralis, ligamen dan otot-otot.[4]
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan anestesi
subaraknoid adalah lokasi medulla spinalis didalam kolumna vertebralis. Medulla
spinalis berjalan mulai dari foramen magnum kebawah hingga menuju ke konus
medularis (segmen akhir medulla spinalis sebelum terpecah menjadi kauda
equina). Penting diperhatikan bahwa lokasi konus medularis bervariasi antara
vertebra T12 hingga L1. [1][4]
Memperhatikan susunan anatomis dari vertebra, ada beberapa landmark
yang lazim digunakan untuk memperkirakan lokasi penting pada vertebra,
diantaranya adalah :
1. Vertebra C7 : Merupakan vertebra servikal dengan penonjolan yang
paling terlihat di daerah leher.
2. Papila Mamae : Lokasi ini kurang lebih berada di sekitar vertebra
torakal 3-4
5
3. Epigastrium : Lokasi ini kurang lebih berada di sekitar vertebra torakal
5-6
4. Umbilikus : Lokasi ini berada setinggi vertebra torakal 10
5. Krista Iliaka : Lokasi ini berada setinggi kurang lebih vertebra
lumbalis 4-5[1][3][6]
Gambar 2 : Perjalanan Medulla Spinalis pada Kolumna Vertebralis[5]
Berikut adalah susunan anatomis pada bagian yang akan dilakukan anestesi spinal.
Kutis
Subkutis : Ketebalannya berbeda-beda, akan lebih mudah mereba ruang
intervertebralis pada pasien yang memiliki lapisan subkutis yang tipis.
Ligamentum Supraspinosum: Ligamen yang menghubungkan ujung
procesus spinosus.
Ligamentum interspinosum
6
Ligamentum flavum : Ligamentum flavum cukup tebal, sampai sekitar 1
cm. Sebagian besar terdiri dari jaringan elastis. Ligamen ini berjalan
vertikal dari lamina ke lamina. Ketika jarum berada dalam ligamen ini,
akan terasa sensasi mencengkeram dan berbeda. Sering kali bisa kita
rasakan saat melewati ligamentum dan masuk keruang epidural.
Epidural : Ruang epidural berisi pembuluh darah dan lemak. Jika darah
yang keluardari jarum spinal bukan CSF, kemungkinan vena epidural telah
tertusuk. Jarum spinal harus maju sedikit lebih jauh.
Duramater : Sensasi yang sama mungkin akan kita rasakan saat menembus
duramater seperti saat menembus epidural.
Subarachnoid : merupakan tempat kita akan menyuntikkan obat anestesi
spinal. Pada ruangan ini akan dijumpai likuor sereberospinalis (LCS) pada
penusukan. [1][4]
Gambar 4 : Susunan Anatomi ligament vertebra[6]
Pembuluh darah pada daerah tusukan juga perlu diperhatikan, terdapat arteri dan
vena yang lokasinya berada di sekitar tempat tusukan. Terdapat arteri Spinalis
posterior yang memperdarahi 1/3 bagian posterior medulla. Arteri spinalis anterior
memperdarahi 2/3 bagian anterior medulla. Terdapat juga adreti radikularis yang
7
memperdarahi medulla, berjalan di foramen intervertebralis memperdarahi radiks.
Sistem vena yang terdapat di medulla ada 2 yaitu vena medularis anterior dan
posterior.
Gambar 5 : Sistem Vaskular Medula Spinalis[7]
II. 5. PERSIAPAN ANESTESI SPINAL
Persiapan yang diperlukan untuk melakukan anestesi spinal lebih
sederhana dibanding melakukan anestesi umum, namun selama operasi wajib
diperhatikan karena terkadang jika operator menghadapi penyulit dalam operasi
dan operasi menjadi lama, maka sewaktu-waktu prosedur secara darurat dapat
diubah menjadi anestesi umum.
Persiapan yang dibutuhkan untuk melakukan anestesi spinal adalah ;
8
Informed consent : Pasien sebelumnya diberi informasi tentang tindakan ini
(informed consent) meliputi tindakan anestesi, kemungkinan yang akan
terjadi selama operasi tindakan ini dan komplikasi yang mungkin terjadi.
Pemeriksaan fisik : Pemeriksaan fisik dilakukan meliputi daerah kulit
tempat penyuntikan untuk menyingkirkan adanya kontraindikasi seperti
infeksi. Perhatikan juga adanya gangguan anatomis seperti scoliosis atau
kifosis,atau pasien terlalu gemuk sehingga tonjolan processus spinosus
tidak teraba.
Pemeriksaan laboratorium anjuran: Pemeriksaan laboratorium yang
perlu dilakukan adalah penilaian hematokrit, Hb , masa protrombin (PT)
dan masa tromboplastin parsial (PTT) dilakukan bila diduga terdapat
gangguan pembekuan darah. (6)(7)
Persiapan yang dibutuhkan setelah persiapan pasien adalah persiapan alat dan
obat-obatan. Peralatan dan obat yang digunakan adalah :
1. Satu set monitor untuk memantau tekanan darah, Pulse oximetri, EKG.
2. Peralatan resusitasi / anestesia umum.
3. Jarum spinal. Jarum spinal dengan ujung tajam (ujung bambu runcing,
quincke bacock) atau jarum spinal dengan ujung pinsil (pencil point
whitecare), dipersiapkan dua ukuran. Dewasa 26G atau 27G
4. Betadine, alkohol untuk antiseptic.
5. Kapas/ kasa steril dan plester.
6. Obat-obatan anestetik lokal.
7. Spuit 3 ml dan 5 ml.
8. Infus set. (6)
Gambar 6 : Jenis Jarum Spinal[7]
9
II.6. OBAT-OBATAN PADA ANESTESI SPINAL
Obat-obatan pada anestesi spinal pada prinsipmnya merupakan obat
anestesi local. Anestetik local adalah obat yang menghambat hantaran saraf bila
dikenakan pada jaringan saraf dengan kadar cukup. Paralisis pada sel saraf akibat
anestesi local bersifat reversible.
Obat anestesi local yang ideal sebaiknya tidak bersifat iritan terhadap
jaringan saraf. Batas keamanan harus lebar, dan onset dari obat harus sesingkat
mungkin dan masa kerja harus cukup lama. Zat anestesi local ini juga harus larut
dalam air.
Terdapat dua golongan besar pada obat anestesi local yaitu golongan amid
dan golongan ester. Keduanya hampir memiliki cara kerja yang sama namun
hanya berbeda pada struktur ikatan kimianya. Mekanisme kerja anestesi local ini
adalah menghambat pembentukan atau penghantaran impuls saraf. Tempat utama
kerja obat anestesi local adalah di membrane sel. Kerjanya adalah mengubah
permeabilitas membrane pada kanal Na+ sehingga tidak terbentuk potensial aksi
yang nantinya akan dihantarkan ke pusat nyeri.[8]
Berat jenis cairan cerebrospinalis pada 37 derajat celcius adalah 1.003-
1.008. Anastetik local dengan berat jenis sama dengan LCS disebut isobaric.
Anastetik local dengan berat jenis lebih besar dari LCS disebut hiperbarik.
10
Anastetik local dengan berat jenis lebih kecil dari LCS disebut hipobarik.
Anastetik local yang sering digunakan adalah jenis hiperbarik diperoleh dengan
mencampur anastetik local dengan dextrose. Untuk jenis hipobarik biasanya
digunakan tetrakain diperoleh dengan mencampur dengan air injeksi. [8]
Berikut adalah beberapa contoh sediaan yang terdapat di Indonesia dan umum
digunakan.
Lidokaine 5% dalam dextrose 7.5%: berat jenis 1.003, sifat hyperbaric,
dosis 20-50mg(1-2ml).
Bupivakaine 0.5% dlm air: berat jenis 1.005, sifat isobaric, dosis 5-20mg.
Bupivakaine 0.5% dlm dextrose 8.25%: berat jenis 1.027, sifat
hiperbarik,dosis 5-15mg(1-3ml).
Obat Anestesi local memiliki efek tertentu di setiap system tubuh manusia.
Berikut adalah beberapa pengaruh pada system tubuh yang nantinya harus
diperhatikan saat melakukan anesthesia spinal.
1. Sistem Saraf : Pada dasarnya sesuai dengan prinsip kerja dari obat anestesi
local, menghambat terjadinya potensial aksi. Maka pada system saraf akan
terjadi paresis sementara akibat obat sampai obat tersebut dimetabolisme.
2. Sistem Respirasi : Jika obat anestesi local berinteraksi dengan saraf yang
bertanggung jawab untuk pernafasan seperti nervus frenikus, maka bisa
menyebabkan gangguan nafas karena kelumpuhan otot nafas.
3. Sistem Kardiovaskular : Obat anestesi local dapat menghambat impuls
saraf. Jika impuls pada system saraf otonom terhambat pada dosis tertentu,
maka bisa terjadi henti jantung. Pada dosis kecil dapat menyebabkan
bradikardia. Jika dosis yang masuk pembuluh darah cukup banyak, dapat
terjadi aritmia, hipotensi, hingga henti jantung. Maka sangat penting
diperhatikan untuk melakukan aspirasi saat menyuntikkan obat anestesi
local agar tidak masuk ke pembuluh darah.
4. Sistem Imun : Karena anestesi local memiliki gugus amin, maka
memungkinkan terjadi reaksi alergi. Penting untuk mengetahui riwayat
alergi pasien. Pada reaksi local dapat terjadi reaksi pelepasan histamine
11
seperti gatal, edema, eritema. Apabila tidak sengaja masuk ke pembuluh
darah, dapat menyebabkan reaksi anafilaktik.
5. Sistem Muskular : obat anestetik local bersifat miotoksik. Apabila
disuntikkan langsung kedalam otot maka dapat menimbulkan kontraksi
yang tidak teratur, bisa menyebabkan nekrosis otot.
6. Sistem Hematologi : obat anestetik dapat menyebabkan gangguan
pembekuan darah. Jika terjadi perdarahan maka membutuhkan penekanan
yang lebih lama saat menggunakan obat anestesi local. [2][8][11]
Dalam penggunaan obat anestesi local, dapat ditambahkan dengan zat lain atau
adjuvant. Zat tersebut mempengaruhi kerja dari obat anestesi local khususnya
pada anestesi spinal. Tambahan yang sering dipakai adalah :
1. Vasokonstriktor : Vasokonstriktor sebagai adjuvant pada anestesi spinal
dapat berfungsi sebagai penambah durasi. Hal ini didasari oleh mekanisme
kerja obat anestesi local di ruang subaraknoid. Obat anestesi local
dimetabolisme lambat di dalam rongga subaraknoid. Dan proses
pengeluarannya sangat bergantung kepada pengeluaran oleh vena dan
saluran limfe. Penambahan obat vasokonstriktor bertujuan memperlambat
clearance obat dari rongga subaraknoid sehingga masa kerja obat menjadi
lebih lama.[6][7][8]
2. Obat Analgesik Opioid : digunakan sebagai adjuvant untuk mempercepat
onset terjadinya fase anestetik pada anestesi spinal. Analgesic opioid
misalnya fentanyl adalah obat yang sangat cepat larut dalam lemak. Hal ini
sejalan dengan struktur pembentuk saraf adalah lemak. Sehingga
penyerapan obat anestesi local menjadi semakin cepat. Penelitian juga
menyatakan bahwa penambahan analgesic opioid pada anestesi spinal
menambah efek anestesi post-operasi.[9][10]
3. Klonidin : Pemberian klonidin sebagai adjuvant pada anestesi spinal dapat
menambah durasi pada anestesi. Namun perlu diperhatikan karena
klonidin adalah obat golongan Alfa 2 Agonis, maka harus diwaspadai
terjadinya hipotensi akibat vasodilatasi dan penurunan heart rate.[10]
12
Dosis obat anestesi regional yang lazim digunakan untuk melakukan anestesi
spinal terdapat pada table dibawah ini.
Tabel 1 : Dosis Obat Untuk Anestesi Spinal[11]
II. 7. TEKNIK ANESTESI SPINAL
Posisi duduk atau posisi tidur lateral dekubitus dengan tusukan pada garis
tengah ialah posisi yang paling sering dikerjakan. Biasanya dikerjakan di atas
meja operasi tanpa dipindah lagi dan hanya diperlukan sedikit perubahan posisi
pasien.
1. Pasang IV line. Berikan Infus Dextrosa/NaCl/Ringer laktat
sebanyak 500 - 1500 ml (pre-loading).
2. Oksigen diberikan dengan kanul hidung 2-4 L/Menit
3. Setelah dipasang alat monitor, pasien diposisikan dengan baik.
Dapat menggunakan 2 jenis posisi yaitu posisi duduk dan
berbaring lateral.
4. Raba krista. Perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua
krista iliaka dengan tulang punggung ialah L4 atau L4-L5.
5. Palpasi di garis tengah akan membantu untuk mengidentifikasi
ligamen interspinous.
6. Cari ruang interspinous cocok. Pada pasien obesitas anda mungkin
harus menekan cukup keras untuk merasakan proses spinosus.
7. Sterilkan tempat tusukan dengan betadine atau alkohol.
13
8. Beri anastesi lokal pada tempat tusukan,misalnya dengan lidokain
1-2% 2-3ml
9. Cara tusukan adalah median atau paramedian. Untuk jarum spinal
besar 22G, 23G atau 25G dapat langsung digunakan. Sedangkan
untuk jarum kecil 27G atau 29G dianjurkan menggunakan
penuntun jarum (introducer), yaitu jarum suntik biasa yaitu jarum
suntik biasa 10cc. Jarum akan menembus kutis, subkutis,
ligamentum supraspinosum, ligamentum interspinosum,
ligamentum flavum, epidural, duramater, subarachnoid. Setelah
mandrin jarum spinal dicabut, cairan serebrospinal akan menetes
keluar. Selanjutnya disuntikkan obat analgesik ke dalam ruang
arachnoid tersebut.[2][6][7]
Gambar 7 : Posisi Lateral pada Spinal Anestesi[7]
Gambar 8 : Posisi Duduk pada Spinal Anestesi[7]
14
Teknik penusukan bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu median dan
paramedian. Pada teknik medial, penusukan dilakukan tepat di garis tengah dari
sumbu tulang belakang. Pada tusukan paramedial, tusukan dilakukan 1,5cm lateral
dari garis tengah dan dilakukan tusukan sedikit dimiringkan ke kaudal.[7]
Gambar 9 : Tusukan Medial dan Paramedial[7]
Setelah melakukan penusukan, tindakan berikutnya adalah melakukan monitoring.
Tinggi anestesi dapat dinilai dengan memberikan rangsang pada dermatom di
kulit. Penilaian berikutnya yang sangat bermakna adalah fungsi motoric pasien
dimana pasien merasa kakinya tidak bisa digerakkan, kaki terasa hangat,
15
kesemutan, dan tidak terasa saat diberikan rangsang. Hal yang perlu diperhatikan
lagi adalah pernapasan, tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah bisa turun
drastis akibat spinal anestesi, terutama terjadi pada orang tua yang belum
diberikan loading cairan. Hal itu dapat kita sadari dengan melihat monitor dan
keadaan umum pasien. Tekanan darah pasien akan turun, kulit menjadi pucat,
pusing, mual, berkeringat.[7]
Gambar 10 : Lokasi Dermatom Sensoris[7]
II.8. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANESTESI SPINAL
Anestesia spinal dipengaruhi oleh beberapa factor. Diantaranya adalah :
Volume obat analgetik lokal: makin besar makin tinggi daerah
analgesia
Konsentrasi obat: makin pekat makin tinggi batas daerah analgesia
16
Barbotase: penyuntikan dan aspirasi berulang-ulang meninggikan
batas daerah analgetik.
Kecepatan: penyuntikan yang cepat menghasilkan batas analgesia
yang tinggi. Kecepatan penyuntikan yang dianjurkan: 3 detik untuk
1 ml larutan.
Maneuver valsava: mengejan meninggikan tekanan liquor
serebrospinal dengan akibat batas analgesia bertambah tinggi.
Tempat pungsi: pengaruhnya besar pada L4-5 obat hiperbarik
cenderung berkumpul ke kaudal (saddle blok) pungsi L2-3 atau L3-
4 obat cenderung menyebar ke cranial.
Berat jenis larutan: hiperbarik, isobarik atau hipobarik
Tekanan abdominal yang meningkat: dengan dosis yang sama
didapat batas analgesia yang lebih tinggi.
Tinggi pasien: makin tinggi makin panjang kolumna vertebralis
makin besar dosis yang diperlukan.(BB tidak berpengaruh terhadap
dosis obat)
Waktu: setelah 15 menit dari saat penyuntikan, umumnya larutan
analgetik sudah menetap sehingga batas analgesia tidak dapat lagi
diubah dengan posisi pasien.[3]
17
BAB III
LAPORAN KASUS
A. IDENTITAS PENDERITA
Nama : Tn. K.A.
Umur : 42 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 11 Juni 2015
Alamat : Lingkungan Gebang
Diagnosis pre operatif : Appendisitis Akut
Diagnosis post operasi : Appendisitis Akut
Macam Operasi : Appendiktomi
Macam Anestesi : Anestesi umum
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh dan tukang
MRS : 09 Juni 2015
Pre Operatif (10 Juni 2015)
a. Anamnesis
Keluhan Utama : Nyeri perut kanan bawah
RPS :
- Onset : kurang lebih 3 bulan yang lalu
- Lokasi : perut kanan bawah
- Kualitas : -
- Kuantitas : keluhan dirasakan hilang timbul
- Faktor yang memperberat dan memperingan : -
- Kronologis : ± 3 hari SMRS hari sebelum masuk rumah sakit, yaitu
hari minggu (9 juni 2015), pasien merasakan nyeri pada perut bagian
kanan bawah dan badannya hangat. Nyeri dirasakan tidak menjalar.
18
Nyeri bertambah bila untuk menekukan kaki. Nyeri bersifat kumat-
kumatan. Belum ada riwayat pengobatan apapun.
- Keluhan penyerta : susah buang air besar
RPD : Asma (-), alergi makanan dan obat (-), HT (-), DM (-)
RPK : -
Riwayat sosial/ekonomi : sehari-hari pasien pergi bekerja dan ditempat
kerja pasien bekerja sebagai buruh tukang
BB : ± 70 kg
TB : ± 165 cm
b. Pemeriksaan fisik
Keadaan Umum : sakit sedang, kompos mentis, gizi cukup
Tensi : 120/ 80 mmHg
Nadi : 78 x/menit
Suhu Axiler : 37,0 C
Respirasi : 20x/menit
Berat badan : 60 kg
Mata : Konjungtiva anemis ( - ), sklera ikterik ( - )
Hidung : nafas cuping hidung ( - ), sekret ( - )
Mulut : sianosis ( - ), gigi goyah / palsu ( - )
Telinga : sekret ( - ), pendengaran baik
Leher : glandula thiroid ditengah, pembesaran limfonodi
( - ), JVP tidak meningkat
Thorax
Pulmo I : Pengembangan paru kanan = kiri
P : Fremitus raba kanan = kiri
P : Sonor - Sonor
A: Suara dasar : vesikuler kanan = kiri
Suara tambahan : wheezing (-)
Jantung I : Ictus cordis tidak tampak
19
P : Ictus cordis tidak kuat angkat
P : Batas jantung kesan tidak melebar
A: Bunyi jantung I-II intensitas normal,
Reguler, bising (-)
Abdomen : I : Dinding perut = dinding dada, distended (-), darm contur
(-), darm steifung (-)
P : Supel, Nyeri tekan (+) pada perut kanan bawah (Mc
Burney Sign (+)),defans muskuler (-)
P : Timpani (+), NKCV (-)
A : Peristaltik (+) normal
Ekstremitas : oedem ( - ), akral dingin (-)
Pemeriksaan Khusus :
Mc Burney sign (+)
Rovsing sign (+)
Rebound Sign (+)
Obturator sign (+)
Psoas sign (-)
Rectal Toucher : TMSA normal, mukosa licin, ampila normal, prostat
tidak teraba membesar, nyrti tekan jam 9,11 (+), massa (-), sarung tangan
lender darah (-), feses (+)
c. Pemeriksaan Penunjang
1. Laboratorium
a. WBC : 8,19 x 103/ul
b. RBC : 5,43 x 106/ul
c. HB : 16,3 gr/dl
d. PLT : 266 x 103/ul
e. PT : 7,46 detik
f. APTT : 1,39 detik
20
2. USG
d. Diagnosis Pre-operasi
- Diagnosis : Appendisitis
- Tindakan : Appendictomi
e. Kesan Anestesi
Laki - Laki 42 tahun menderita appendisitis dengan ASA I
21
f. Terapi Pre-operasi
1. Puasa 6 jam pre-operasi
2. Inform consent ke keluarga tentang resiko tinggi operasi
3. IVFD RL 20 TPM
4. Oksigenasi 3 lpm (kanul)
5. Cefoperazon 1 gr / 8jam
6. Premed metil prednisolon 125 mg, Ranitidin 1 amp
g. Kesimpulan
Pasien seorang laki-laki, usia 42 tahun, dengan keluhan utama
nyeri perut kanan bawah, dan didiagnosa : appendisitia akut. Dari
pemeriksaan fisik didapatkan : Vital Sign : tekanan darah 120/80 mmHg,
nadi 78x/menit, respirasi rate 20x/menit, suhu axiller 37,0oC, BB 60 kg.
Cor dan pulmo dalam batas normal, abdomen: didapatkan nyeri kanan
bawah, Mc Burney Sign (+)
Pada pemeriksaan laboratorium darah didapatkan
a. WBC : 8,19 x 103/ul
b. RBC : 5,43 x 106/ul
c. HB : 16,3 gr/dl
d. PLT : 266 x 103/ul
e. PT : 7,46 detik
f. APTT : 1,39 detik
g. GDS 126 mg/dL
Akan dilakukan appendictomi dengan anestesi regional (spinal).
Kelainan sistemik : (-), Kegawatan bedah : (+), Status fisik : ASA I
(Pasien sehat secara Jasmani dan Rohani, tidak ada gangguan sistemik.
ACC Operasi
22
B. RENCANA ANESTESI
1. Persiapan operasi
a. Persetujuan operasi tertulis ( + )
b. Periksa tanda vital dan keadaan umum
c. Puasa > 6 jam
d. Oksigenasi 3 L / menit
e. Cek obat dan alat anestesi
f. Infus RL 20 tpm makro
2. Jenis anestesi :
Anestesi regional (spinal).
3. Mulai Anestesi : 11 Juni 2015, Pukul 10.00 WITA
Mulai Operasi : 11 Juni 2015, Pukul 10.15 WITA
4. Premedikasi yang diberikan :
5 menit sebelum dilakukan induksi anestesi, pasien diberikan Ondancetron
(Cedantron) 4 mg.
5. Anestesi yang diberikan :
Induksi anestesi (pukul 10.00):
Dilakukan penyuntikan Bupivacain (Bunascan) 125 mg dengan jarum
spinal ke ruang subarachnoid antara kanalis spinalis VL 4 – VL 5. dan
setelahnya diberikan phetidin 50 mg iv
6. Pemeliharaan (Maintenance):
Selama tindakan anestesi berlangsung, tekanan darah dan denyut nadi
selalu dimonitor. Infus RL diberikan pada penderita sebagai cairan
rumatan. Beberapa saat sebelum operasi selesai diberikan Ketorolac
tromethamin (Remopain 3 %) 2,5 cc IV sebagai analgesik setelah operasi.
23
Waktu O2 HR TD SaO2 Obat Ket
10.00
8 L 107 135/83 99
Ondansentron
4mg
Midazolam 2mg
Kanul
10.15
(mulai
operasi)
4 L 110 130/80 99
Tramadol
100mg
Ketorolak 30mg Kanul
10.30 4 L 85 112/65 99 -
10.45 4 L 85 129/70 99 -
7. Keadaan pasca operasi :
Operasi selesai dalam waktu 45 menit (pukul 10.45).
8. Ruang Recovery :
Pasien dipindah ke ruang rumatan dan diawasi aktivitas motorik, sensorik
dan kesadaran. Bila pasien tenang dengan Aldrette Score > 8 tanpa nilai
nol, maka pasien dapat dipindah ke bangsal. Pada pasien ini, Aldrette
Score bernilai 8, dengan rincian sebagai berikut:
1. Warna kulit merah muda (nilai 2)
2. Pasien dapat bernapas dalam dan teratur (nilai 2)
3. Tekanan darah + 20 % dari tekanan darah praanestesi (nilai 2)
4. Pasien bangun bila dipanggil (nilai 1)
5. Ekstremitas atas dapat digerakkan (nilai 1)
9. Program pasca operasi :
Setelah pasien memiliki Aldrette Score > 8, pasien dikirim ke bangsal
dengan catatan:
- Awasi tanda vital secara ketat
- Awasi kesadaran
- Mual muntah berikan ondansentron 4 mg / 8 jam
- Program cairan (RL 20 TPM)
- Cek Hb pasca operasi
24
- Jika kaki pasien dapat digerakkan dan pasien sadar penuh, minum
bertahap
- Program analgetik (Tramadol 100 mg dan ketorolac 30 mg) injeksi IV/
8 jam mulai jam 17.00, bila kesakitan dapat diberikan lebih awal
- Pemberian antibiotik (Cefotaxim)
- Program khusus : 1) pasien tidur dengan bantal tinggi / head up 30% /
Bedrest total selama 24 jam, 2) bila TD sistl < 90 mmHg, Injeksi
efedrin 10 mg, 3) Bila HR < 60 x/m, injeksi Sulfas Atropin 2 ampul
- Lain-lain sesuai dokter bedah
- Keadaan gawat darurat, hubungi dokter anestesi
25
BAB IV
PEMBAHASAN
Dari hasil kunjungan pra anestesi baik dari anamnesa, pemeriksaan fisik
akan dibahas masalah yang timbul, baik dari segi medis, bedah maupun anestesi.
A. PERMASALAH DARI SEGI MEDIK
Appendisitis yang merupakan proses radang dapat meningkatkan
metabolisme, dimana kebutuhan cairan meningkat yang menyebabkan penderita
mengalami kehilangan banyak cairan sehingga bisa terjadi dehidrasi atau juga
sepsis.
B. PERMASALAHAN DARI SEGI BEDAH
1. Operasi yang jika tidak dilakukan pembedahan, bisa mengancam jiwa
pasien, terutama jika terapi obat tidak respon dapat timbul perforasi.
2. Kemungkinan perdarahan durante dan post operasi, sehingga perlu
dipersiapkan darah.
3. Iatrogenik (resiko kerusakan organ akibat pembedahan)
Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dipersiapkan jenis dan
teknik anestesi yang aman untuk operasi yang lama.
C. PERMASALAHAN DARI SEGI ANESTESI
1. Pemeriksaan pra anestesi
Pada penderita ini telah dilakukan persiapan yang cukup, antara lain :
a. Puasa lebih dari 6 jam.
b. Pemeriksaan laboratorium darah
Permasalahan yang ada adalah :
Bagaimana memperbaiki keadaan umum penderita sebelum dilakukan
anestesi dan operasi.
Macam dan dosis obat anestesi yang bagaimana yang sesuai dengan
keadaan umum penderita.
26
Dalam memperbaiki keadaan umum dan mempersiapkan operasi pada
penderita perlu dilakukan :
Pemasangan infus untuk terapi cairan sejak pasien masuk RS.
Puasa paling tidak 6 jam untuk mengosongkan lambung, sehingga
bahaya muntah dan aspirasi dapat dihindarkan.
Pada operasi pasien ini, teknik anestesi yang digunakan adalah anestesi
regional (spinal). Sebagai premedikasi dipakai Midazolam (Miloz) dan
Ondancetron (Cedantron).
Midazolam dapat digunakan sebagai premedikasi dengan dosis sedatif
(0,1 mg/kgBB) maupun sebagai analgesi anestesi dengan dosis 5-10 mg. Pada
pasien ini digunakan Midazolam sebagai dosis sedatif yaitu sebanyak 1,5 mg.
Ondancetron digunakan sebagai antiemetik sebanyak 4 mg yang diberikan
secara intravena.
Ketamin (ketalar) kurang digemari untuk induksi anestesi karena sering
menimbulkan takikardi, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala dan mual-
muntah pasca anestesia, pandangan kabur serta mimpi buruk. Ketamin juga
dapat menimbulkan halusinasi, oleh karena itu sebelumnya perlu diberikan
sedasi berupa Midazolam atau Diazepam dengan dosis 0,1 mg/kgBB dan
untuk mengurangi salivasi diberikan sulfas atropin 0,01 mg/kgBB. Dosis
induksi intravena ialah 1-2 mg/kgBB dan untuk intramuskular 3-10 mg. Pada
pasien ini Ketamin digunakan untuk analgesi dengan dosis 15mg, agar pada
saat melakukan spinal anestesi, pasien tidak merasakan sakit.
Induksi dilakukan dengan menggunakan Bupivacain (Bunascan) 125 mg
dengan jarum spinal ke ruang subarachnoid antara kanalis spinalis VL3 –
VL4. Selama tindakan anestesi berlangsung, tekanan darah dan denyut nadi
selalu dimonitor. Infus RL diberikan pada penderita sebagai cairan rumatan.
Beberapa saat sebelum operasi selesai diberikan Ketorolac tromethamin
(Remopain 1 %) 10 mg IV sebagai analgesik setelah operasi
27
BAB V
KESIMPULAN
Pada makalah ini disajikan kasus penatalaksanaan anestesi regional
(spinal) pada operasi elektif appendictomy pada pasien laki-laki, umur 42 tahun,
status fisik ASA I. Dengan diagnosis appendicitis dengan menggunakan teknik
anestesi regional (spinal)
Subarachnoid Spinal Block, sebuah prosedur anestesi yang efektif dan bisa
digunakan sebagai alternatif dari anestesi umum. Anestesi ini bekerja setinggi
papilla mamae atau setinggi kurang lebih vertebra torakal 4. Prinsip yang
digunakan adalah menggunakan obat analgetik local untuk menghambat hantaran
saraf sensorik untuk sementara (reversible). Fungsi motoric juga terhambat
sebagian. Dan pada teknik anestesi ini, pasien tetap sadar.
Terdapat indikasi dan kontra indikasi yang terbagi dua yaitu kontraindikasi
absolut dan relative. Pada kontraindikasi relative anestesi tetap bisa dilakukan
dengan memperhatikan hal-hal tertentu seperti kemungkinan komplikasi dan
alternative lain jika tidak bisa dilakukan anestesi spinal. Seluruh persiapan wajib
dicermati mulai dari persiapan pasien, alat, obat anestesi local, obat emergensi
yang harus disediakan jika terjadi komplikasi, hingga kemungkinan untuk
mengganti prosedur menjadi anestesi umum seketika prosedur anestesi spinal
tidak berjalan dengan baik. Saat penusukan diperlukan ketelitian untuk
menentukan lokasi suntikan, kemudian memperhatikan pendekatan untuk
melakukan penusukan serta memperhatikan factor yang mempengaruhi anestesi.
Prosedur ini merupakan sebuah alternative pada operaasi dengan durasi
singkat. Pilihan ini menyediakan opsi yang memiliki komplikasi yang lebih
sedikit ketimbang melakukan prosedur anestesi umum diantaranya adalah waktu
pemulihan pasca-dilakukan posedur anestesi.
28
DAFTAR PUSTAKA
1. Muhardi, M, dkk. (2002). Anestesiologi, bagian Anastesiologi dan Terapi Intensif, FKUI, CV Infomedia, Jakarta.
2. Tony H., (2000). Anestesi umum dalam Farmakologi dan Terapi, edisi IV. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
3. Boulton T.H., Blogg C.E., (1999). Anesthesiology, cetakan I. EGC, Jakarta.
4. Morgan G.E., Mikhail M.S., (1992). Clinical Anesthesiology. 1st ed. A large medical Book
5. Wim de Jong, (1996) Buku Ajar lmu Bedah, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
6. Wirjoatmojo, K, (2000). Anestesiologi dan Reanimasi Modul Dasar Untuk Pendidikan S1 Kedokteran, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7. Dobson Michael B, (1994)Penuntun Praktis Anestesi, cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
29