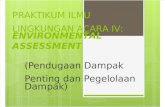klimatQ ACARA IV
-
Upload
danank-d-lite -
Category
Documents
-
view
492 -
download
4
Transcript of klimatQ ACARA IV
ACARA IV MENENTUKAN IKLIM SUATU TEMPAT
I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Iklim dapat didefinisikan sebagai ukuran statistik cuaca untuk jangka waktu tertentu dan cuaca menyatakan status atmosfer pada sembarang waktu tertentu. Cuaca dan iklim di Indonesia memiliki karakteristik khusus. Dua unsur utama iklim adalah suhu dan curah hujan. Indonesia sebagai daerah tropis ekuatorial mempunyai variasi suhu yang kecil, sementara variasi curahnya cukup besar. Oleh karena itu curah hujan merupakan unsur iklim yang sering diamati dibandingkan dengan suhu. Pada praktikum kali ini data curah hujan dan suhu digunakan untuk menentukan iklim yang diambil dari stasiun meteorologi Sempor,Kebumen, Jawa Tengah. Penggolongan iklim ini antara lain menurut Mohr, Schmidt-Fergusson, Oldeman, dan Koppen. B. TUJUAN
1. Melatih mahasiswa menyatukan berbagai anasir iklim guna menentukan tipe iklim. 2. Melatih mahasiswa mengetahui hubungan tipe iklim dengan keadaan tanaman setempat.
II.
TINJAUAN PUSTAKA
Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau dikatakan iklim merupakan rata-rata cuaca. Menurut persetujuan internasional data yang digunakan adalah harga rata-rata cuaca selama 30 tahun. Sebetulnya jumlah iklim di permukaan bumi ini hampir tidak terbatas sehingga memerlukan penggolongan dalam suatu kelas atau tipe. Perlu diketahui bahwa semua klasifikasi iklim itu buatan manusia sehingga masing-masing ada kebaikan dan keburukannya, tetapi mereka memiliki persamaan tujuan yaitu berusaha untuk menyederhanakan iklim yang tidak terbatas jumlahnya itu menjadi golongan yang jumlahnya relatif sedikit yaitu kelas-kelas yang mempunyai sifat yang penting bersamaan (Wisnubroto, 1981). Keadaan iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi. Indonesia terletak di daerah equator (7o LU-11o LS) dan diapit oleh benua Asia dan Australia. Benua Asia dan Australia termasuk monsoon foci yang menyebabkan adanya dua periode musim yaitu musim hujan dan kemarau di Indonesia disebabkan peresebaran curah hujan di Indonesia tidak merata ini dikarenakan sebaran pulau dan gunung yang banyak. Dengan melihat keadaan iklim yang khas itu, maka untuk menentukan tipe iklim di Indonesia diperlukan metode klasifikasi tersendiri. Klasifikasi secara empirik iklim dapat dibagi dua yaitu klasifikasi iklim berdasarkan Rational Moisture Budget (Thornthwaite) dengan memasukkan pengertian penguapan, karena tumbuhan hidup tidak hanya tergantung pada curah hujan saja, tetapi juga oleh uap air. Apabila penguapan melebihi curah hujan yang jatuh, maka keadaan seperti ini tidak ada gunanya bagi tumbuhan dan yang kedua adalah dengan klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi alami (Sutarno, 1998). Iklim telah terbagi sesuai lokasi atau daerah yang telah dideterminasikan tidak hanya untuk satu elemen saja, tetapi dengan variasi kombinasi variabel meteorologi. Dua tempat mungkin memililki temperatur yang sama, tetapi ada perbedaan curah hujan di sana. Beberapa karakteristik dari distribusi iklim telah diketahui melalui klasifikasi secara astronomi. Ada beberapa klasifikasi iklim sesuai parameter pengukurannya yaitu klasifikasi menurut Mohr, Schmidt dan Fergusson, Oldeman, dan Koppen. Di antara keempat jenis klasifikasi iklim ini terdapat persamaan dan perbedaan (Harwitz, 1944). Untuk mengetahui periode kering di suatu daerah Schmid dan Fergusson menghitung nilai Q didasarkan kriteria kering, cukup dan lembab menurut batasan Mohr. Tetapi karena angka yang digunakan terlampau rendah maka untuk keperluan pertanian hendaknya digunakan secara hati-hati. Hingga saat ini kekeringan masih sulit untuk diberikan batasan yang dapat digunakan
untuk semua keperluan pertanian, karena tiap jenis tanah, tanaman dan kondisi iklim tertentu mempunyai batas tertentu pula untuk mencapai tingkat kekeringan (Sutrisno dan Sumiratno, 1983). Pertanian sebaiknya mempertimbangkan sumber iklim, proses eksploitasi untuk memperoleh hasil, peternakan dan peralatan (mesin) yang digunakan. Pada proses penyerapan permukaan tanah, dalam tahapan-tahapan yang akan dilalui tergantung pada elemen-elemen ini. Jangka waktu pertanian yang dipengaruhi sumber iklim menunjukkan iklim sangat penting pada ilmu pertanian (William, 1983). Peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau dan musim hujan lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai dengan kondisi iklim aktual. Perubahan musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator penciri musim untuk menentukan apakah wilayah berada pada periode musim hujan, memasuki musim hujan, musim kemarau, dan memasuki musim kemarau. Berdasar permasalahan anomali iklim dan iklim bulanan utuk meminimalkan resiko pertanian, maka ada tiga hal yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu (Irianto, 2003) : 1. Analisis perkembangan iklim dengan indikator penciri perubahan musim. 2. Analisis perkiraan curah hujan menggunakan teknik Kalman filter. 3. Diseminasi informasi anomali iklim dan mitigasinya kepada pengambil kebijakan.
III. METODOLOGI
Praktikum Menentukan Iklim Suatu Tempat dilakukan pada hari Selasa, 4 Oktober 2011, di laboratorium Agroklimat Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Bahan yang digunakan adalah data curah hujan (CH ) selama 10 tahun pada stasiun Sempor,kebumen,jawa tengah, dan data rerata suhu udara (T) bulanan. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menganalisis iklim daerah setempat menurut sistem klasifikasi Mohr, Schmidt-Fergusson, Oldeman dan Koppen. Untuk klasifikasi berdasarkan Mohr pertama kali dibuat kolom curah hujan (CH) per tahun, urah hujan (CH) rerata, dan Derajat Kebasahan Bulan (DKB). Kemudian data yang didapat dikasukkan ke dalam tabel dan dihitung curah hujan rerata dan dimasukkan dalam kolom DKB. Dan dihitung jumlah bulan basah (BB), bulan lembab (BL), dan bulan kering (BK). Kemudian ditentukan iklim daerah setempat menurut penggolongan iklim menurut Mohr. Untuk klasifikasi Schmidt-Fergusson pertama kali dibuat tabel dengan kolom bulan, curah hujan per tahun dengan kolom DKB pada setiap kolom tahun. Semua data dimasukkan dalam tabel, lalu ditentukan DKB tiap data dan dimasukkan dalam kolom DKB, lalu dihitung jumlah BB, BL, dan BK tiap tahun dan dihitung nilai Q dengan rumus Q =rerataBK dan iklim setempat ditentukan rerataBB
menurut penggolongan iklim Schmidt-Fergusson. Untuk klasifikasi Oldeman, pertama kali dibuat tabel dengan kolom-kolom seperti yang digunakan pada klasifikasi Mohr. Semua data dimasukkan pada tabel dan DKB dalam setiap data ditentukan menurut kriteria Mohr. Jumlah rerata BB, BL, dan BK dihitung dalam angka bulat, dan tipe iklim suatu daerah setempat ditentukan dengan Sistem Klasifikasi Agroklimat. Sedangkan untuk klasifikasi Koppen, dilakukan dengan menghitung rerata BB, BL, dan BK. Selain itu untuk klasifikasi Koppen dibutuhkan tabel identifikasi tipe iklim untuk menentukan suatu tipe iklim.
IV. HASIL PENGAMATAN PEMBAHASAN A. HASIL PENGAMATAN.
Stasiun : Sempor Lintang : 7 LS Evaluasi: 114m dpl Tahun 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1. Jan 407 543 814 0 6 264 522 701 337 447 Feb 367 456 352 419 474 286 296 514 199 577 Mar 327 616 321 226 487 463 788 289 286 326 Apr 418 387 267 182 447 361 317 119 92 0 Mei 79 429 4 633 471 75 77 143 339 156 Jun 7 277 7 10 91 181 267 65 479 458 Jul 63 115 5 0 77 21 146 27 23 231 Ags 190 125 0 0 75 90 189 29 22 151 Sep 25 118 0 1 522 54 452 7 167 0 Okt 598 499 5 405 306 278 259 12 518 266 Nop 650 518 80 770 455 689 814 633 398 205 Des 274 541 392 355 629 186 238 842 331 283
HASIL PERHITUNGAN. a. Sistem klasifikasi Mohr. Data Curah Hujan Rerata Bulan Sejenis (mm).Jan 2579 257,9 BB Feb 1061 117,8 BB Mar 3050 338,8 BB Apr 3377 375,2 BB Mei 3066 306,6 BB Jun 1792 179,2 BB Jul 1982 220,2 BB Ags 1585 176,1 BB Sep 3619 361,9 BB Okt 3577 357,7 BB Nop 4390 439 BB Des 2666 266,5 BB
DKB
*Tipe iklim Golongan I : Daerah basah, dengan CH melebihi penguapan selama 12 bulan. Hampir tanpa bulan kering. b. Sistem klasifikasi Schmit dan Fergusson.Tahun 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Jan BB BL BB BB BB BB BB BB BB BB Peb BK BB BK BB BB BB BK BL BK BK Mar BK BB BB BB BB BB BB BB BB BB Apr BK BB BB BB BB BB BB BB BB BL Mei BB BB BB BB BL BB BB BB BB BB Jun BB BB BB BB BB BB BB BB BK BB Jul BK BB BK BB BB BB BK BB BB BB Ags BB BB BK BK BK BB BK BB BB BB Sep BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Okt BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Nov BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Des BB BB BB BB BB BB BB BB BL BB BB 8 11 9 11 10 12 9 11 9 10 100 10 BL 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 1 BK 4 0 3 1 1 0 3 0 2 1 15 2,14
Rerata BK
2,14
Q= Rerata BB
= 10
= 0,214
Tipe iklim Golongan B : Daerah basah , vegetasi hutan hujan tropis.
c. Sistem Klasifikasi Oldeman.Tahu n 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Jan BL BK BB BB BB BB BL BB BB BB Peb BK BB BK BL BB BB BK BK BK BK Mar BK BB BL BB BB BL BL BB BB BB Apr BK BB BB BB BB BL BB BB BB BK Mei BB BB BL BB BK BB BB BB BB BL Jun BL BL BL BL BL BL BB BB BK BB Jul BK BL BK BB BB BB BK BL BB BB Ags BL BL BK BK BK BB BK BB BB BL Sep BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Okt BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB Nov BL BB BB BB BB BB BB BB BL BB Des BB BB BB BB BB BB BB BB BB BL BB 4 8 6 9 9 9 7 10 8 7 77 7,7 8 BL 4 3 3 2 1 3 2 1 1 2 22 2,2 2 BK 4 1 3 1 2 3 1 3 3 21 2,1 2
Tipe iklim Golongan B2 : Daerah dengan 7-8 BB berurutan. Perlu perencanaan teliti untuk penanaman sepanjang tahun.
d. Klasifikasi Koppen Suhu tahunan dengan rumus empiris : Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember T max 30,8-0,0062x3=30,78 312,7-0,0061x3=31,68 31,1-0,0062x3=31,08 31,4-0,0061x3=31,38 31,4-0,0061x3=31,38 31,2-0,0061x3=31,28 31,1-0,0061x3=31,08 31,5-0,0061x3=31,48 32,0-0,0062x3=31,98 32,2-0,0064x3=32,18 32,2-0,0064x3=32,18 31,0-0,0062x3=30,98 =376,36 31,36 T min 23,3-0,0054x3=23,28 23,3-0,0053x3=23,29 22,9-0,0054x3=23,28 22,9-0,0052x3=22,88 22,9-0,0051x3=22,88 22,7-0,0051x3=22,68 21,6-0,0051x3=21,58 22,0-0,0052x3=21,98 22,3-0,0054x3=22,28 22,3-0,0055x3=22,28 22,8-0,0055x3=22,78 23,3-0,0054x3=23,28 =272,47 =22,70
T rerata = T max + T min 2 = 31,36+22,70 = 27,03 C
B. PEMBAHASAN Iklim dari suatu tempat terdiri dari unsur-unsur yang variasinya sangat berbeda jauh, dan dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin bila dua tempat mempunyai iklim yang identik. Jumlah iklim di permukaan bumi ini hampir tidak terbatas, sehingga membutuhkan penggolongan ke dalam suatu kelas atau tipe. Klasifikasi iklim yang dibuat oleh manusia tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun pengklasifikasian iklim tersebut dapat memudahkan dalam mengidentifikasi iklim pada suatu daerah, karena pengklasifikasian iklim tersebut menyederhanakan jumlah iklim lokal yang tidak terbatas jumlahnya menjadi beberapa golongan yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu kelas-kelas yang mempunyai sifat penting yang bersamaan. Sistem klasifikasi iklim menurut Mohr, pembagian iklim menurut Mohr ditentukan oleh jumlah bulan basah dan bulan kering suatu tempat untuk tiap-tiap bulan. Bulan basah merupakan bulan yang curah hujannya dalam 1 bulan lebih dari 100 mm. Untuk lokasi sempor, terjadi hampir tiap bulan berkisar mulai 117,8 mm sampai 490 mm.Hasil tersebut adalah rata-rata setiap bulan untuk periode tahun 1980 sampai tahun 1989. Berdasarkan metode Mohr dapat diketahui bahwa daerah yang berada di Sempor,termasuk golongan I yaitu daerah dengan Ch melebihi penguapan selama 12 bulan, hampir tanpa periode kering (BL antara 1-6)..
Metode Mohr ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah walaupun jenis tanah tidak menjadi dasar sistem klasifikasi Mohr sudah cukup mewakili berbagai jenis tanah, metode ini telah diterapkan dengan berhasil pada daerah tropis seperti Trinidad, bahkan adapula yang diterapkan dalam bentuk variasi seperti di Konyo. Sistem klasifikasi ini menyajikan data curah hujan bulanan dapat diketahui pergeseran iklim tiap bulan Kekurangannya adalah pengklasifikasiannya didasarkan pada rata-rata bulanan sehingga kurang sesuai untuk memberi gambaran secara sempurna mengenai keadaan iklim Indonesia, tidak mengikutsertakan sifat fisis suatu tanah yang juga dapat memberi pengaruh pada penetuan iklim. Selain itu, dengan metode klasifikasi ini, tidak dapat diketahui pergeseran iklim tiap tahun, dasar penentuannya hanya dari curah hujan sehingga hanya dapat digunakan untuk menentukan iklim di daerah dengan curah hujan stabil maupun periodik. Sistem klasifikasi menurut Schmidt-Fergusson, penentuan iklim menggunakan harga perbandingan Q, yaitu jumlah rerata bulan kering dengan jumlah rerata bulan basah. Untuk mendapatkan rerata bulan basah dan rerata bulan kering, masing-masing bulan pada tiap tahun ditentukan kategorinya apakah bulan basah atau bulan kering. Kemudian bulan basah dan bulan kering tersebut dihitung jumlahnya kemudian masing-masing bulan basah dan bulan kering tersebut dibagi 10. dari hasil perhitungan data dari tahun 1980 sampai tahun 1989 diperoleh jumlah bulan basah sebanyak 100 bulan lembab sebanyak 5 dan bulan kering sebanyak 15. Setelah dibagi 10, selanjutnya dicari nilai Q. Didapatkan nilai Q sebesar 0,214. Nilai tersebut menurut metode Schmidt-Fergusson terletak antara 0,143 60 mm. Tipe iklim ini berkarakter bulan terpanas datang pada saat sottice dan musim hujan summer. Berdasar curah hujan, pada iklim ini semua bulan termasuk pada bulan basah karena curah hujannya merata dan tinggi intensitasnya. Kelebihan dari klasifikasi iklim menurut Koppen adalah dasar curah hujan dan ada tambahan suhu tahunan, kelebihan sistem klasifikasi ini adalah terletak dalam penyusunan simbol-simbol tipe iklim yang dengan tepat merumuskan sifat dan curah masing-masing tipe iklim dengan tanda yang terdiri dari kombinasi beberapa huruf saja yang dapat dengan tepat merumuskan sifat dan corak iklim suatu wilayah. Sedangkan, kekurangan sistem klasifikasi ini adalah sistem klasifikasi iklim ini hanya dapat dilihat vegetasi asli, namun belum menjelaskan tanaman produksi yang cocok, serta kurang memperhitungkan tanah dimana vegetasi asli berada. Klasifikasi ini juga kurang tepat dalam penentuan pola tanam.
V. KESIMPULAN 1. Iklim merupakan gabungan kondisi cuaca sehari-hari atau merupakan rata-rata curah hujan, yaitu selama 30 tahun. Klasifikasi ini dapat dibedakan secara genetis dan secara empirik. 2. Klasifikasi iklim di Indonesia pada umumnya tergantung curah hujan. Tipe iklim di Indonesia sesuai dengan klasifikasi Mohr, tipe iklim di Indonesia untuk daerah Sempor, Kebumen, Jawa Tengah adalah : A. Menurut Klasifikasi Mohr pada golongan I sebab daerahnya basah dengan curah hujan melebihi penguapan selama 12 bulan, hampir tanpa periode kering (BL antara 1-6) B. Menurut klasifikasi Schmidt dan Fergusson termasuk golongan B, yaitu daerah basah dengan vegetasi hutan hujan tropis. C. Menurut klasifikasi Oldeman termasuk zone B, daerah dengan 7 - 8 BB berurutan subdivisinya 2 sehingga perlu perencanaan teliti dalam penanaman satu tahun penuh. D. Menurut klasifikasi Koppen termasuk daerah Af yaitu iklim hujan tropis basah merupakan daerah iklim basah, suhu rerata bulanan lebih dari 18C dan sekurangkurangnya satu bulan dengan curah hujan lebih dari 60mm. 3. Sistem klasifikasi iklim yang cocok untuk Indonesia adalah metode Koppen.
DAFTAR PUSTAKA
Harwitz, Benhard, and James M. Austin.1994. Climatology. Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York and London. Irianto, G. 2003. Model prediksi anomali iklim untuk mengurangi resiko pertanian. http://www.baitklimat.litbang.deptan.go.id. Diakses pada 6 Oktober 2011. Sutarno, M.T. 1998. Klimatologi Dasar. UPN Veteran Press. Yogyakarta. Sutrisno dan Sumiratno. 1983. Model Analisis Air Tanah. Prosiding Seminar Berkala Meteorologi dan Geofisika Desember 82 April 2003. Departemen Perhubungan Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta. Williams, G. D. V. 1983. Agroclimatic resource and analysis an example using a index derived and applied for Canada. Agricultural Meteorological Journal, XXVIII (1), halaman: 31-47. Wisnubroto, S., Mulyono N., Rosich A. dan Anjal A.A. 1998. Stasiun Meteorologi Pertanian dan Keabsahan Data Edisi ke-2. Laboratorium Agroklimatologi, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.