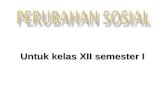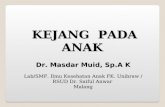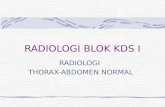KDS Restu
-
Upload
restuningdiah-dwi-s -
Category
Documents
-
view
29 -
download
2
description
Transcript of KDS Restu

BAB I
KASUS
I. IDENTITAS PASIEN
Nama : An. NRS
Umur : 15 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Masuk RS : 9 Maret 2013 Jam : 22.00
Nama Ayah : Bp. S Nama Ibu : Ibu. J
Umur : 30 tahun Umur : 26 tahun
Pekerjaan : Buruh Pekerjaan : IRT
Pendidikan : STM Pendidikan : SMA
Alamat : Jetis, Bantul
Diagnosis masuk : Kejang Demam Sederhana et causa Diare Cair Akut
tanpa dehidrasi DD - Kejang Demam Kompleks
- Epilepsi
- Ensefalitis
- Meningitis
- Metabolic disorder
II. RIWAYAT PENYAKIT
Alloanamnesis dilakukan dengan ibu pasien
Tanggal : 9 Maret 2013
1. Keluhan Utama : Demam dan kejang
Keluhan Tambahan: BAB cair
2. Riwayat Penyakit Sekarang :
Anak datang ke IGD RSPS dengan keluhan demam sejak 10 jam SMRS. Demam
awalnya tidak begitu tinggi, kemudian naik perlahan, saat suhu tubuh 39 C anak
kejang sebanyak 1 kali (2 jam SMRS). Kejang seluruh tubuh, mulut tidak berbusa,
tangan kaku. Menurut ibunya kejang berlangsung sekitar 30 detik. Saat kejang anak
tidak mengigau, setelah kejang anak diam lalu menangis. Anak juga BAB cair warna
kekuningan sebanyak 4x setelah demam, volume kurang lebih setengah gelas tiap
1

BAB, ampas (+) tanpa lendir dan darah. Muntah(+) 1x,sesak nafas (-), batuk (-),
pilek(-),minum mau, anak sulit untuk makan, BAK terakhir 1 jam SMRS.
3. Riwayat Penyakit Dahulu
Anak tidak memiliki riwayat kejang saat demam, maupun kejang tanpa demam
sebelumnya.
4. Riwayat penyakit pada keluarga yang diturunkan atau ditularkan
Riwayat demam dengan kejang : Ayah anak pernah kejang dengan demam
ketika bayi.
Riwayat kejang tanpa demam : disangkal
Kesan : Terdapat riwayat kejang dengan demam pada keluarga.
5. Riwayat Pribadi
a. Riwayat Kehamilan
Ibu kontrol teratur setiap bulan ke bidan dan mendapat tablet tambah darah dan
vitamin. Obat selalu habis diminum. Selama hamil ibu dinyatakan sehat, mual-mual
(+), riwayat sakit (-), bengkak – bengkak pada tungkai (-), perdarahan pervaginam (-).
Ibu tidak pernah mengkonsumsi jamu-jamuan, tidak merokok ataupun mengkonsumsi
obat-obatan.Ibu mendapat suntikan TT 2x selama hamil di bidan. Ibu menyangkal
memiliki penyakit hipertensi, diabetes melitus, asma dan jantung.
b. Riwayat Persalinan
Lahir di bidan usia kehamilan 38 minggu, dengan berat badan lahir 3000 kg, anak
lahir spontan langsung menangis kuat. Warna air ketuban jernih, dan bayi tidak biru
ataupun kuning.
c. Riwayat Pasca Persalinan
Anak dapat menetek kuat, anak tidak kuning, tidak biru, anak tidak sesak napas,
tidak kejang-kejang.
Kesan : Riwayat kehamilan cukup baik, riwayat persalinan baik dan riwayat pasca
persalinan baik.
d. Riwayat Makanan
Usia Kualitas Kuantitas
0 – 4 bulan ASI Diberikan sesuka bayi
5 – 7 bulanASI
Bubur susu
Diberikan sesuka bayi
3 x sehari, 1 piring kecil
8 – 11 bulan ASI Diberikan sesuka bayi
2

Nasi tim 3 x sehari, 1 piring kecil
Kesan : Kualitas dan kuantitas makanan sudah cukup
e. Vaksinasi
BCG, Hepatitis B, DPT, Polio, Campak imunisasi lengkap sesuai PPI
( Pengembangan Program Imunisasi).
f. Riwayat Penyakit Dahulu
Dari lahir, pasien pernah mengalami batuk, pilek, dan diare.
Kesan : Tidak terdapat riwayat penyakit dahulu pada pasien yang berhubungan
dengan riwayat penyakit sekarang.
g. Anamnesis Sistem
- Sistem saraf pusat : demam (+), kejang (-), penurunan kesadaran (-)
- Sistem kardiovaskuler : sesak (-), biru (-)
- Sistem respiratori : batuk (-), pilek (-), sesak nafas (-)
- Sistem gastrointestinal : muntah (+), kembung (-), diare cair ampas (+)
- Sistem urogenital : BAK (+) normal
- Sistem integumental : kulit kuning (-), pucat (-), Turgor melambat (-)
- Sistem musculoskeletal : gerakan (+) bebas, lumpuh (-), kejang (-)
III. PEMERIKSAAN FISIK
Kesan Umum
Keadaan Umum : Tampak sakit sedang
Tanda Vital : Nadi : 116 x/menit, isi dan tegangan cukup teratur
Suhu : 38,50 C (saat masuk Rumah Sakit)
Pernafasan : 30 x/menit, tipe : torakal
Status gizi : BB : 11 Kg, umur : 15 bulan
Menurut klasifikasi status gizi anak BALITA, berdasarkan
(BB/U) pada anak laki-laki, termasuk gizi baik.
Kebutuhan kalori : BB x faktor kebutuhan berdasarkan umur
11 x 100 kkal = 1100 kkal/hari
Protein = 110 kkal = 27,5 gram
Lemak = 220 kkal = 24,4 gram
Karbohidrat = 770 kkal = 192,5 gram
Pemeriksaan kepala
Bentuk kepala : Normochepal
3

Ubun-ubun : Tertutup, cembung (-)
Mata : Cekung (-/-), discharge (-/-), conjungtiva anemis (-/-)
Pupil: Reflek cahaya (+/+), isokor (+/+)
Hidung : Discharge (-/-), deformitas (-/-),epistaksis (-/-)
Telinga : Otore (-/-), nyeri tekan (-/-)
Mulut : pucat (-), lidah kotor (-), mukosa bibir kering (-)
Pharing : Hiperemis (-)
Leher :Limfonodi tidak teraba, kaku kuduk (-), Pembesaran kelenjar
tiroid (-), retraksi suprasternal (-)
Pemeriksaan Thorax :
Depan Inspeksi Simetris, retraksi (-), ketinggalan gerak (-)
Palpasi Vokal fremitus kanan = kiri, ketinggalan gerak (-)
Perkusi Sonor di kedua bagian paru
Auskultasi Vesikuler (+) normal, ronkhi (-), wheezing (-)
Belakang Inspeksi Simetris, retraksi (-), ketinggalan gerak (-)
Palpasi Vokal fremitus kanan = kiri, ketinggalan gerak (-)
Perkusi Sonor di kedua bagian paru
Auskultasi Vesikuler (+) normal, ronkhi (-), wheezing (-)
Jantung :
Inspeksi : Iktus kordis tidak tampakPalpasi : Iktus kordis teraba pada sela iga ke 5 linea
midclavicula kiri, teraba tidak kuat angkatPerkusi : Batas jantung
Kanan atas : SIC II linea para sternalis kanan.
Kiri atas : SIC II linea para sternalis kiri.Kanan bawah : SIC IV linea para sternalis
kanan.Kiri bawah : SIC V linea midklavikula kiri.
Auskultasi : S1 & S2 reguler, Bising jantung (-)Pemeriksaan Abdomen :
Inspeksi : Datar, simetris
Auskultasi : Peristaltik (+)↑
Perkusi : Timpani
Palpasi : Supel, turgor dan elastisitas baik, hepar dan lien tidak teraba
4

Kulit : sianosis (-), pucat (-), turgor dan elastisitas baik
Kelenjar limfe : limfonodi tidak teraba
Otot : eutrofi
Tulang : fraktur (-), deformitas (-), gerak bebas (+)
Sendi : tanda radang (-), gerak bebas (+)
Anogenital : Laki-laki, anus (+), tidak ada kelainan.
Ekstremitas :
Lengan kanan/kiri Gerakan : Bebas/Bebas
Tonus : Normal/Normal
Trofi : Eutrofi/Eutrofi
Tungkai Kanan/Kiri Gerakan : Bebas/Bebas
Tonus : Normal/Normal
Trofi : Eutrofi/Eutrofi
Refleks Fisiologis :
Refleks patella : (+) normal / (+) normal
Refleks biceps : (+) normal / (+) normal
Refleks triceps : (+) normal / (+) normal
Refleks Patologis :
Refleks babinski : (-)/(-)
Refleks hoffman : (-)/(-)
Refleks oppenheim : (-)/(-)
Refleks chadock : (-)/(-)
Meningeal Sign :
Kaku kuduk : (-)
Brudzinski I : (-)
Brudzinski II : (-)
Kernig : (-)
5

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG
Darah Rutin :
- Laboratorium Darah
Hb 13,2 gr% N = 13 – 17 g%
AL 8,7 ribu/ul N = 9 – 12 ribu/ul
AE 4,83 juta/ul N = 4,5 – 5,5 juta/ul
AT 356 ribu/ul N = 150 – 450 ribu/ul
Hmt 32,8 % N = 37 – 47 %
Hitung Jenis Leukosit:
Eosinofil 1 % N = 2 – 4%
Basofil 0 % N = 0 – 1%
Batang 0 % N = 2 – 5%
Segmen 53 % N = 51 – 67%
Limfosit 39 % N = 20 – 35%
Monosit 7 % N = 4 – 8%
Natrium 136,3 135 – 148 mmol/l
Kalium 3,59 3,5 – 5,3 mmol/l
Clorida 106,1 98 – 107 mol/l
V. DIAGNOSIS KERJA Kejang Demam Sederhana Diare Cair Akut tanpa dehidrasi Status Gizi Baik
VI. TERAPISupportif :Infus KAEN 3B 8 tpmRehidrasi Plan A :Pemberian minuman sebanyak semau anak, lanjutkan pemberian ASIUsia < 2 tahun : intake cairan 50-100 ml tiap BABUsia > 2 tahun : intake cairan 100-200 ml tiap BABMedikamentosa :- Diazepam rectal 5 mg jika kejang (Dosis 0,5 mg/kg BB/kali)- PO Diazepam 1 mg bila suhu >38,5 C (Dosis 0,1 mg/kgBB/kali)- PO Zink 1x20 mgSimptomatik :- Parasetamol syrup 1 cth (jika panas) (Dosis 10 mg/kg BB/kali)
6

Edukatif :
- Meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis yang baik
- Memberitahukan cara penanganan dan pencegahan kejang
- Kompres hangat anak tiap kali suhu tubuh meningkat
- Memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali
- Jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan.
- Cebok menggunakan sabun.
- Penyediaan air minum yang bersih dan memasak air hingga mendidih.
- Menjaga kebersihan makanan.
VII. FOLLOW UP
Hari S O P
09/03/13 Anak datang ke IGD RSPS dengan keluhan
demam sejak 10 jam SMRS. Demam awalnya
tidak begitu tinggi, kemudian naik perlahan, saat
suhu tubuh 39 C anak kejang sebanyak 1 kali (2
jam SMRS). Kejang seluruh tubuh, mulut tidak
berbusa, tangan kaku. Menurut ibunya kejang
berlangsung sekitar 30 detik. Saat kejang anak
tidak mengigau, setelah kejang anak diam lalu
menangis. Anak juga BAB cair warna
kekuningan sebanyak 4x setelah demam, volume
kurang lebih setengah gelas tiap BAB, ampas (+)
tanpa lendir dan darah. Muntah(+) 1x,sesak nafas
(-), batuk (-), pilek(-),minum mau tapi hanya
sebentar-sebentar dan tidak begitu banyak, anak
sulit untuk makan, BAK terakhir 1 jam SMRS.
Ass : Kejang demam sederhana e.c DCA tanpa
dehidrasi
Status gizi baik
KU : tampak sakit
sedang, Compos
mentis.
T: 38,0 oC
N: 116 x/menit
RR : 30 x/menit
Mata: cekung(-/-),
sekret(-/-).
Hidung: Nafas
cuping hidung (-),
sekret (-).
Telinga: Sekret
(-/-)
Thorax: simetris,
vesikuler +/+,
retraksi -/-, S1 S2
reguler.
Abd: Turgor kulit
baik, nyeri tekan-,
peristaltic +
meningkat.
-Infus Kaen 3B 8
tpm
-Injeksi Cefotaxim
3x400 mg
-PO Diazepam 1
mg (T > 38,5 C)
-PO Sanmol 1 cth
k/p
- PO Zinc 1x20 mg
Diet 3xbubur
7

Akral Hangat,
CRT<2s
Kaku Kuduk (-/-)
10/03/13 Anak sudah tidak demam, kejang (-), BAB cair
(+) 2x, lendir (-), darah (-),muntah (-),batuk
pilek(-), BAK lancar, makan dan minum mau.
Ass : Kejang demam sederhana e.c DCA tanpa
dehidrasi
Status gizi baik
KU : Compos
mentis
T: 36,8 oC
N: 100 x/m
RR : 26x/m
Mata cekung
(-/-),sekret(-/-).
Hidung: Nafas
cuping hidung (-),
sekret (-).
Telinga: Sekret
(-/-)
Thorax: Simetris,
Vesikuler +/+,
retraksi -/-, S1 S2
reguler.
Abd: Turgor kulit
baik, nyeri tekan-,
peristaltic +
meningkat.
Akral Hangat,
CRT<2s
Kaku Kuduk (-/-)
-Infus Kaen 3B 8
tpm
-Injeksi Cefotaxim
3x400 mg
-PO Diazepam 1
mg (T > 38,5 C)
-PO Sanmol 1 cth
k/p
- PO Zinc 1x20 mg
Diet 3xbubur
11/03/13 Kejang (-), BAB jemek 1x , lendir (-), darah (-),
muntah(-), batuk pilek(-), BAK lancar, makan
dan minum mau.
KU : Compos
mentis
T: 36,5 oC
N: 112 x/m
RR : 26 x/menit
Mata:
-Infus Kaen 3B 8
tpm
-Injeksi Cefotaxim
3x400 mg
-PO Diazepam 1
mg (T > 38,5 C)
8

Ass : Kejang demam sederhana e.c DCA tanpa
dehidrasi
Status gizi baik
konjungtivaanemis(
-/-), cekung
(-/-),sekret(-/-).
Hidung: Nafas
cuping hidung (-),
sekret (-).
Telinga: Sekret
(-/-)
Thorax: Simetris,
Vesikuler +/+,
retraksi -/-, S1 S2
reguler.
Abd: Turgor kulit
normal, nyeri
tekan-, peristaltic +
normal.
Akral Hangat,
CRT<2s
Kaku Kuduk (-/-)
-PO Sanmol 1 cth
k/p
- PO Zinc 1x20 mg
Diet 3xbubur
12/3/13 Kejang (-), BAB Normal, Jemek (-) cair (-)
lendir(-),darah(-), muntah(-), batuk pilek(-),
BAK lancar, makan dan minum mau.
Ass : Kejang demam sederhana e.c DCA tanpa
dehidrasi
Status gizi baik
KU : Compos
mentis
T: 36,3 oC
N: 102 x/menit
RR : 26 x/menit
Mata:
konjungtivaanemis(
-/-), cekung
(-/-),sekret(-/-).
Hidung: Nafas
cuping hidung (-),
sekret (-).
Telinga: Sekret
(-/-)
-Infus Kaen 3B 8
tpm
-Injeksi Cefotaxim
3x400 mg
-PO Diazepam 1
mg (T > 38,5 C)
-PO Sanmol 1 cth
k/p
- PO Zinc 1x20 mg
Diet 3xbubur
9

Pulmo: Simetris,
Vesikuler +/+,
retraksi -/-, S1 S2
reguler.
Abd: Turgor kulit
normal, nyeri
tekan-, peristaltic +
normal.
Akral Hangat,
CRT<2s
Kaku Kuduk (-/-)
10

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
I. KEJANG DEMAM
A. DEFINISI
1.1. Kejang
Sebelum kita memahami definisi mengenai kejang, perlu kita ketahui tentang
seizure dan konvulsi. Yang dimaksud dengan seizure adalah cetusan aktivitas
listrik abnormal yang terjadi secara mendadak dan bersifat sementara di antara saraf-
saraf di otak yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, kerja otak menjadi terganggu.
Manifestasi dari seizure bisa bermacam-macam, dapat berupa penurunan kesadaran,
gerakan tonik (menjadi kaku) atau klonik (kelojotan), konvulsi dan
fenomena psikologis lainnya. Kumpulan gejala berulang dari seizure yang terjadi
dengan sendirinya tanpa dicetuskan oleh hal apapun disebut sebagai epilepsi (ayan).
Sedangkan konvulsi adalah gerakan mendadak dan serentak otot-otot yang tidak bisa
dikendalikan, biasanya bersifat menyeluruh. Hal inilah yang lebih sering dikenal
orang sebagai kejang. Jadi kejang hanyalah salah satu manifestasi dari seizure.
1.2. Kejang Demam
Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh
(suhu rektal di atas 38oC) tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat atau gangguan
elektrolit akut, terjadi pada 2 – 4 % anak antara umur 6 bulan – 5 tahun (menurut:
consensus statement on febrile seizures). Puncaknya umur 14 – 18 bulan, 30 %
diantaranya pernah mengalami kejang demam sebelumnya. 33 % anak yang pernah
mengalami kejang demam akan mengalami recurensi 1 kali, dan 9 % anak dengan
riwayat kejang demam akan mengalami recurensi 3 kali atau lebih. Kejang disertai
demam pada bayi berumur kurang dari 1 bulan tidak termasuk kejang demam. Bila
anak berumur kurang dari 6 bulan atau lebih dari 5 tahun mengalami kejang didahului
demam, kemungkinan lain harus dipertimbangkan misalnya infeksi SSO atau epilepsi
yang kebetulan terjadi bersama demam.
B. EPIDEMIOLOGI
Hampir sebanyak 1 dari setiap 25 anak pernah mengalami kejang demam dan
lebih dari sepertiga dari anak-anak tersebut mengalaminya lebih dari 1 kali. Kejang
11

demam terjadi pada anak dengan umur berkisar antara 6 bulan sampai 5 tahun,
insidensi tertinggi pada umur 18 bulan. Sebanyak 80% merupakan kejang demam
sederhana, sedangkan 20% merupakan kejang demam kompleks.
C. ETIOLOGI
Penyebab yang pasti dari terjadinya kejang demam tidak diketahui. Faktor resiko
kejang demam yang penting adalah demam. Namun kadang-kadang demam yang
tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang. Selain itu terdapat faktor resiko lain,
seperti riwayat kejang demam pada orang tua atau saudara kandung, perkembangan
terlambat, problem pada masa neonatus, anak dalam perawatan khusus, dan kadar
natrium rendah. Kejang demam biasanya berhubungan dengan demam yang tiba-tiba
tinggi dan kebanyakan terjadi pada hari pertama anak mengalami demam. Dalam
literatur disebutkan bahwa infeksi oleh virus herpes simpleks manusia 6 (HHSV-6) yang
merupakan penyebab dari Roseola sering menjadi penyebab pada 20 % pasien kejang demam
serangan pertama. Disentri karena Shigella juga sering menyebakan demam tinggi dan kejang
demam pada anak-anak. Dan pada sebuah studi dibicarakan mengenai adanya hubungan antara
kejang demam yang berulang dengan infeksi virus influenza A. Demam dapat muncul pada
permulaan penyakit infeksi (extra Cranial), yang disebabkan oleh banyak macam
agent, antara lain :
1. Infeksi Bakteri
a. Penyakit pada Tractus Respiratorius :
-Pharingitis
-Tonsilitis
-Otitis Media
-Laryngitis
-Bronchitis
-Pneumonia
b. Penyakit pada Tractus Gastro Intestinal Tractus :
-Dysenteri Baciller, Shigellosis
c. Penyakit pada Tractus Urogenitalis :
-Pyelitis, Cystitis, Pyelonephritis
12

2. Infeksi Virus
Terutama yang disertai exanthema :
-Varicella
-Morbili
-Dengue
-Exanthema subitum
D. PATOFISIOLOGI
Untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau organ otak diperlukan energi
yang didapat dari metabolisme. Bahan baku yang digunakan berupa glukosa yang
akan dipecah menjadi CO2 dan air.
Dalam keadaan normal membran neuron dapat dilalui dengan mudah oleh ion
Kalium (K+) dan sulit oleh ion Natrium (Na+) kecuali Clorida (Cl-). Akibatnya K+
tinggi dalam sel dan Na+ rendah, sedangkan di luar sel sebaliknya. Perbedaan ini yang
membentuk potensial membran sel neuron. Sebuah potensial aksi akan terjadi akibat
adanya perubahan potensial membrane sel yang didahului dengan stimulus membran
sel neuron. Saat depolarisasi, channel ion Na+ terbuka dan channel ion K+ tertutup.
Hal ini menyebabkan influx dari ion Na+, sehingga menyebabkan potensial membran
sel lebih positif, sehingga terbentuklah suatu potensial aksi. Dan sebaliknya, untuk
membuat keadaan sel neuron repolarisasi, channel ion K+ harus terbuka dan channel
ion Na+ harus tertutup, agar dapat terjadi efluks ion K + sehingga mengembalikan
potensial membran lebih negatif atau ke potensial membrane istirahat.
Untuk menjaga keseimbangan potensial membran sel diperlukan energi dan enzim
Na-K-ATP ase yang terdapat di permukaan sel. Keseimbangan potensial membran ini
dapat dirubah oleh:
-Perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler.
-Rangsangan yang datangnya mendadak, misalnya mekanis .
-Perubahan patofisiologi membran sendiri karena penyakit atau keturunan.
13

Gambar 1. Ion Na+ dan K+
Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1oC akan mengakibatkan kenaikan
metabolisme basal 10-15 % dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada
kenaikan suhu tubuh tertentu akan terjadi perubahan keseimbangan dari membran
potensial neuron dan dalam waktu singkat akan terjadi difusi dari K+ dan Na+ melalui
membran tadi dengan akibat lepasnya muatan listrik yang sedemikian besarnya dapat
meluas ke seluruh sel neurotransmitter pada tubuh dan terjadilah kejang.
Tiap anak mempunyai ambang kejang yang berbeda. Pada anak dengan ambang
kejang rendah, kejang telah terjadi pada suhu 38 oC sedangkan pada anak dengan
ambang kejang yang tinggi kejang baru terjadi pada suhu 40 oC. Bangkitan kejang
tergantung pada ambang kejang tersebut yaitu lebih banyak pada anak dengan
ambang kejang rendah. Terulangnya kejang demam lebih sering terjadi pada anak
dengan ambang kejang rendah. Kejang demam yang berlangsung singkat umumnya
tidak berbahaya dan tidak meninggalkan gejala sisa. Tetapi kejang demam yang
berlangsung lama (>15 menit) biasanya disertai dengan apneu, meningkatnya
kebutuhan oksigen dan energi untuk kontraksi otot skeletal yang mengakibatkan
hipoksemia, hiperkapneu, dan asidosis laktat. Hipotensi arterial disertai dengan
aritmia jantung dan kenaikan suhu tubuh disebabkan meningkatnya aktivitas berakibat
14

meningkatnya metabolisme otak. Berikut bagan patofisiologi demam dan terjadinya
kejang demam :
sumber : emedicine
15

E. KLASIFIKASI
Unit Kerja Koordinasi Neurologi IDAI 2006 membuat klasifikasi kejang demam
pada anak menjadi :
a. Kejang Demam Sederhana (Simple Febrile Seizure)
-Kejang demam berlangsung singkat
-Durasi kurang dari 15 menit dan frekuensi bangkitan kejang dalam 1 tahun
tidak lebih dari 4 kali.
-Kejang dapat umum, tonik, dan atau klonik
-Umumnya akan berhenti sendiri
-Tanpa gerakan fokal
-Tidak berulang dalam 24 jam
-Pemeriksaan neurologis sebelum dan sesudah kejang normal
b. Kejang Demam Kompleks (Complex Febrile Seizure)
-Kejang lama dengan durasi lebih dari 15 menit.
-Kejang bersifat fokal atau parsial satu sisi, atau kejang umum didahului
kejang parsial.
-Berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam (diantara 2 bangkita kejang anak
sadar kembali) dan frekuensi kejang lebih dari 3 kali/tahun.
Kejang lama adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang
berulang lebih dari 2 kali dan diantara bangkitan anak tidak sadar. Kejang lama terjadi
pada 8% kejang demam.
Tipe Kejang
Kejang diklasifikasikan sebagai parsial atau generalisata berdasarkan apakah
kesadaran utuh atau lenyap. Kejang dengan kesadaran utuh disebut sebagai kejang
parsial. Kejang parsial dibagi lagi menjadi parsial sederhana (kesadaran utuh) dan
parsial kompleks (kesadaran berubah tetapi tidak hilang).
1. Kejang parsial
Kejang parsial dimulai di suatu daerah di otak, biasanya korteks serebrum.
Gejalakejang ini tergantung pada lokasi fokus di otak. Sebagai contoh, apabila focus
16

terletak di korteks motorik, maka gejala utama mungkin adalah kedutan otot;
sementara, apabila fokus terletak di korteks sensorik, maka pasien mengalami gejala ±
gejala sensorik termasuk baal, sensasi seperti ada yang merayap, atau seperti tertusuk-
tusuk. Kejang sensorik biasanya disertai beberapa gerakan klonik, karena dikorteks
sensorik terdapat beberapa reprsentasi motorik. Gejala autonom adalahkepucatan,
kemerahan, berkeringat, dan muntah. Gangguan daya ingat, disfagia, dan déjà vu
adalah contoh gejala psikis pada kejang parsial. Sebagian pasien mungkin mengalami
perluasan ke hemisfer kontralateral disertai hilangnya kesadaran.Lepas muatan kejang
pada kejang parsial kompleks ( dahulu dikenal sebagai kejang psikomotot atau lobus
temporalis ) sering berasal dari lobus temporalis medial ataufrontalis inferior dan
melibatkan gangguan pada fungsi serebrum yang lebih tinggiserta proses-proses
pikiran, serta perilaku motorik yang kompleks. Kejang ini dapatdipicu oleh musik,
cahaya berkedip-kedip, atau rangsangan lain dan sering disertaioleh aktivitas motorik
repetitif involunta yang terkoordinasi yang dikenal sebagai perilaku otomatis
( automatic behavior ).
Contoh dari perilaku ini adalah menarik-narik baju, meraba-raba benda, bertepuk
tangan, mengecap-ngecap bibir, ataumengunyah berulang-ulang. Pasien mungkin
mengalami perasaan khayali berkabut seperti mimpi. Pasien tetap sadar selama
serangan tetapi umumnya tidak dapat mengingat apa yang terjadi. kejang parsial
kompleks dapat meluas dan menjadi kejang generalisata.
2. Kejang Generalisata
Kejang generalisata melibatkan seluruh korteks serebrum dan diensefalon
sertaditandai dengan awitan aktivitas kejang yang bilateral dan simetrik yang terjadi
dikedua hemisfer tanpa tanda-tanda bahwa kejang berawal sebagai kejang fokal.
Pasientidak sadar dan tidak mengetahui keadaan sekeliling saat mengalami kejang.
Kejangini i muncul tanpa aura atau peringatan terlebih dahulu. Terdapat beberapa tipe
kejanggeneralisata antara lain kejang absence, kejang tonik-klonik, kejang
mioklonik,kejang atonik, kejang tonik dan kejang klonik.
a.Kejang absence ( petit mal )
Ditandai dengan hilangnya kesadaran secara singkat, jarang berlangsung lebihdari
beberapa detik. Sebagai contoh, mungkin pasien tiba-tiba menghentikan pembicaraan,
menatap kosong, atau berkedip-kedip dengan cepat. Pasienmungkin mengalami satu
atau dua kali kejang sebulan atau beberapa kali sehari. Kejang absence hampir selalu
17

terjadi pada anak; awitan jarang dijumpai setelah usia 20 tahun. Serangan-serangan ini
mungkin menghilang setelah pubertas atau
diganti oleh kejang tipe lain, terutama kejang tonik-klonik.
b.Kejang tonik-klonik ( grand mal )
Kejang tonik-klonik adalah kejang epilepsi yang klasik. Kejang tonik-
klonik diawali oleh hilangnya kesadaran dengan cepat. Pasien mungkin
bersuaramenangis, akibat ekspirasi paksa yang disebabkan oleh spasme toraks ata
uabdomen. Pasien kehilangan posisi berdirinya, mengalami gerakan tonik kemudian
klonik, dan inkontenesia urin atau alvi ( atau keduanya ), disertai disfungsi autonom.
Pada fase tonik, otot-otot berkontraksi dan posisi tubuh mungkin berubah. Fase ini
berlangsung beberapa detik. Fase klonik memperlihatkan kelompok-kelompok otot
yang berlawanan bergantian berkontraksi dan melemas sehingga terjadi gerakan-
gerakan menyentak. Jumlah kontraksi secara bertahap berkurang tetapi kekuatannya
tidak berubah. Lidah mungkin tergigit; hal ini terjadi pada sekitar separuh pasien
( spasme rahang dan lidah ). Keseluruhan kejang berlangsung 3 sampai 5 menit dan
diikuti oleh periode tidak sadar yang mungkin berlangsung beberapa menit sampai
selama 30 menit.Setelah sadar pasien mungkin tampak kebingungan, agak stupor,
atau bengong. Tahap ini disebut sebagai periode pascaiktus. Umumnya pasien tidak
dapat mengingat kejadian kejangnya. Kejang tonik-klonik demam, yang sering
disebut sebagai kejang demam, paling sering terjadi pada anak berusia kurang dari 5
tahun. Teori menyarankan bahwa kejang ini disebabkan oleh hipernatremia yang
muncul secara cepat yang berkaitan dengan infeksi virus atau bakteri. Kejang ini
umumnya berlangsung singkat, dan mungkin terdapat predisposisi familial. Pada
beberapa kasus, kejang dapat berlanjut melewati masa anak dan anak mungkin
mengalami kejag non demam pada kehidupan selanjutnya.
Gambar 2. Kejang Tonik-Klonik
18

c.Kejang mioklonik
Kontraksi mirip syok mendadak yang terbatas dibeberapa otot atau
tungkai,cenderung singkat.
d.Kejang atonik
Hilangnya secara mendadak tonus otot disertai lenyapnya postur tubuh.
e.Kejang klonik
Gerakan menyentak, repetitif, tajam, lambat, dan tunggal atau multipel di
lengan,tungkai, atau torso.
f.Kejang tonik
Peningkatan mendadak tonus otot (menjadi kaku, kontraksi) wajah dan
tubuh bagian atas, fleksi lengan dan ekstensi tungkai, mata dan kepala mungkin
berputar ke satu sisi, dapat menyebabkan henti nafas.
F. FAKTOR RESIKO
1. Demam.
2. Usia dan Jenis Kelamin
3. Faktor riwayat kejang demam pada orang tua atau saudara kandung.
4. Kerlambatan perkembangan.
5. Masalah pada waktu neonatus.
6. Anak yang dalam perawatan khusus.
G. MANIFESTASI KLINIS
a. Demam cepat dan tinggi (≥ 39° C).
b. Kejang menyeluruh, tonik-klonik, tonik, klonik, fokal atau akinetik. Lamanya beberapa detik sampai 10 menit (biasanya 1 – 3 menit), berhenti sendiri, tanpa memiliki kelainan neurologis.
c. Gigi atau rahang tertutup rapat.
d. Gangguan pernapasan, apnoe.
e. Sianosis.
f. Inkontinensia.
g. Lidah atau gigi tergigit.
Setelah mengalami kejang anak biasanya:
- Akan kembali sadar dalam waktu beberapa menit atau tertidur selama 1 jam atau lebih.
- Terjadi amnesia (tidak ingat apa yang telah terjadi) - sakit kepala.
- Mengantuk
- Linglung (sementara dan sifatnya ringan).
19

H. DIAGNOSIS
1. Anamnesis :
Adanya kejang, jenis kejang, kesadaran, lama kejang, suhu sebelum /
saatkejang, frekuensi, interval, pasca kejang, penyebab kejang di luar SSP.
Riwayat kelahiran, perkembangan, kejang demam dalam keluarga, epilepsy
dalam keluarga.
Singkirkan dengan anamnesis penyebab kejang yang lain.
2. Pemeriksaan Fisik
Kesadaran
Suhu Tubuh
Tanda Peningkatan Tekanan Intracranial : Kesadaran menurun, muntah proyektil, fontanela
anterior menonjol.
Pemeriksaan Neurologis : Tidak didapatkan kelainan.
Tanda Infeksi di luar SSP : otitis media akut, tonsillitis, bronchitis,
furunkulosis, dll.
3. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan Laboratorium :
Pemeriksaan rutin tidak dianjurkan. Pemeriksaan ini dilakukan sesuai indikasi
untuk mencari penyebab kejang demam atau mengevaluasi sumber infeksi atau
keadaan lain misalnya gastroenteritis dehidrasi disertai demam. Pemeriksaan dapat
meliputi darah perifer lengkap, gula darah, elektrolit serum (Kalsium, fosfor,
magnesium), ureum, kreatinin, urinalisis, biakan darah, urin,atau feses.
Pemeriksaan Radiologi :
X-ray kepala, CT scan kepala atau MRI tidak rutin dan hanya dikerjakan atas
indikasi. Pemeriksaan pencitraan dapat diindikasikan pada keadaan :
Adanya riwayat atau tanda klinis trauma kepala
Kemungkinan adanya lesi structural di otak (mikrosefal, spastisitas)
Adanya tanda peningkatan tekanan intrakranial (kesadaran menurun,
muntah berulang, fontanel anterior menonjol, paresis saraf otak, atau edema
papil)
Kelainan neurologik fokal yang menetap
Pemeriksaan cairan serebrospinal (CSS) :
20

Tindakan pungsi lumbal untuk pemeriksaan CSS dilakukan untuk menegakkana
tau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Pada bayi kecil, klinis meningitis tidak
jelas, maka tindakan pungsi lumbal dikerjakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Bayi < 12 bulan : diharuskan.2. Bayi antara 12 ± 18 bulan : dianjurkan.3. Bayi > 18
bulan : tidak rutin, kecuali bila ada tanda-tanda meningitis.
Pemeriksaan Elektro Ensefalografi (EEG) :
Pemeriksaan EEG tidak diindikasikan pada kejang demam sederhana karena
sebagian besar mempunyai gambaran EEG yang normal. Tidak direkomendasikan,
kecuali pada kejang demam yang tidak khas (misalnya kejang demam kompleks pada
anak usia > 6 tahun atau kejang demam fokal. Pemeriksaan ini biasanya
dipertimbangkan pada keadaan kejang demam kompleks, kejang fokal, dan kesadaran
menurun.
I. TREATMENT
Tujuan pengobatan kejang demam pada anak adalah untuk :
• Mencegah kejang demam berulang
• Mencegah status epilepsi
• Mencegah epilepsi dan / atau mental retardasi
• Normalisasi kehidupan anak dan keluarga.
1. Pengobatan Fase Akut
Anak yang sedang mengalami kejang, prioritas utama adalah menjaga agar jalan
nafas tetap terbuka. Pakaian dilonggarkan, posisi anak dimiringkan untuk mencegah
aspirasi. Sebagian besar kasus kejang berhenti sendiri, tetapi dapat juga berlangsung
terus atau berulang. Pengisapan lendir dan pemberian oksigen harus dilakukan teratur,
kalau perlu dilakukan intubasi. Keadaan dan kebutuhan cairan, kalori dan elektrolit
harus diperhatikan.
Suhu tubuh dapat diturunkan dengan kompres air hangat (diseka) dan pemberian
antipiretik (asetaminofen oral 10 mg/kg BB, 4 kali sehari atau ibuprofen oral 20
mg/kg BB,4 kali sehari).
Saat ini diazepam merupakan obat pilihan utama untuk kejang demam fase akut,
karena diazepam mempunyai masa kerja yang singkat. Diazepam dapat diberikan
21

secara intravena atau rectal, jika diberikan intramuskular absorbsinya lambat. Dosis
diazepam pada anak adalah 0,3-0,5 mg/kg BB, diberikan secara intravena pada kejang
demam fase akut, tetapi pemberian tersebut sering gagal pada anak yang lebih kecil.
Jika jalur intravena belum terpasang, diazepam dapat diberikan per rektal dengan
dosis 5 mg bila berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg pada berat badan lebih dari
10 kg. Pemberian diazepam secara rektal aman dan efektif serta dapat pula diberikan
oleh orang tua di rumah. Bila diazepam tidak tersedia, dapat diberikan luminal
suntikan intramuskular dengan dosis awal 30 mg untuk neonatus, 50 mg untuk usia 1
bulan – 1 tahun, dan 75 mg untuk usia lebih dari 1 tahun. Midazolam intranasal (0,2
mg/kg BB) telah diteliti aman dan efektif untuk mengantisipasi kejang demam akut
pada anak. Kecepatan absorbsi midazolam ke aliran darah vena dan efeknya pada
sistem syaraf pusat cukup baik; Namun efek terapinya masih kurang bila
dibandingkan dengan diazepam intravena.
22

Berikut ini adalah algoritma penanganan kejang :
Sumber : IDAI, 2006
23

2. Mencari dan Mengobati Penyebab
Kejang dengan suhu badan yang tinggi dapat terjadi karena faktor lain, seperti
meningitis atau ensefalitis. Oleh sebab itu pemeriksaan cairan serebrospinal
diindikasikan pada anak pasien kejang demam berusia kurang dari 2 tahun, karena
gejala rangsang selaput otak lebih sulit ditemukan pada kelompok umur tersebut. Pada
saat melakukan pungsi lumbal harus diperhatikan pula kontra indikasinya.1-3
Pemeriksaan laboratorium lain dilakukan atas indikasi untuk mencari penyebab,
seperti pemeriksaan darah rutin, kadar gula darah dan elektrolit. Pemeriksaan CT-
Scan dilakukan pada anak dengan kejang yang tidak diprovokasi oleh demam dan
pertama kali terjadi, terutama jika kejang atau pemeriksaan post iktal menunjukkan
abnormalitas fokal.
3. Pengobatan Profilaksis Terhadap Kejang Demam Berulang
Pencegahan kejang demam berulang perlu dilakukan, karena menakutkan
keluarga dan bila berlangsung terus dapat menyebabkan kerusakan otak yang
menetap.
Terdapat 2 cara profilaksis, yaitu :
• Profilaksis intermittent pada waktu demam
• Profilaksis terus menerus dengan antikonvulsan tiap hari.
1. Profilaksis Intermittent pada Waktu Demam
Pengobatan profilaksis intermittent dengan anti konvulsan segera diberikan pada
waktu pasien demam (suhu rektal lebih dari 38,5ºC). Pilihan obat harus dapat cepat
masuk dan bekerja ke otak. Antipiretik saja dan fenobarbital tidak mencegah
timbulnya kejang berulang. Rosman dkk meneliti bahwa diazepam oral efektif untuk
mencegah kejang demam berulang dan bila diberikan intermittent hasilnya lebih baik
karena penyerapannya lebih cepat. Diazepam diberikan melalui oral atau rektal. Dosis
per rectal tiap 8 jam adalah 5 mg untuk pasien dengan berat badan kurang dari 10 kg
dan 10 mg untuk pasien dengan berat badan lebih dari 10 kg. Dosis oral diberikan 0,5
mg/kg BB perhari dibagi dalam 3 dosis, diberikan bila pasien menunjukkan suhu
38,5oC atau lebih. Efek samping diazepam adalah ataksia, mengantuk dan hipotoni.
Martinez dkk, dikutip dari Soetomenggolo dkk menggunakan klonazepam sebagai
obat anti konvulsan intermittent (0,03 mg/kg BB per dosis tiap 8 jam) selama suhu
24

diatas 38oC dan dilanjutkan jika masih demam. Ternyata kejang demam berulang
terjadi hanya pada 2,5% dari 100 anak yang diteliti. Efek samping klonazepam yaitu
mengantuk, mudah tersinggung, gangguan tingkah laku, depresi, dan salivasi
berlebihan. Tachibana dkk, dikutip dari Soetomenggolo dkk meneliti khasiat
kloralhidrat suppositoria untuk mencegah kejang demam berulang. Dosis yang
diberikan adalah 250 mg untuk berat badan kurang dari 15 kg, dan 500 mg untuk
berat badan lebih dari 15 kg, diberikan bila suhu diatas 38oC. Hasil yang didapat
adalah terjadinya kejang demam berulang pada 6,9% pasien yang menggunakan
supositoria kloralhidrat dibanding dengan 32% pasien yang tidak menggunakannya.
Kloralhidrat dikontraindikasikan pada pasien dengan kerusakan ginjal, hepar,
penyakitjantung, dan gastritis.
2. Profilaksis Terus Menerus dengan Antikonvulsan Tiap Hari
Indikasi pemberian profilaksis terus menerus pada saat ini adalah:
• Sebelum kejang demam yang pertama sudah ada kelainan atau gangguan
perkembangan neurologis.
• Terdapat riwayat kejang tanpa demam yang bersifat genetik pada orang tua atau
saudara kandung.
• Kejang demam lebih lama dari 15 menit, fokal atau diikuti kelainan neurologis
sementara atau menetap.
• Kejang demam terjadi pada bayi berumur kurang dari 12 bulan atau terjadi kejang
multipel dalam satu episode demam.
Antikonvulsan profilaksis terus menerus diberikan selama 1 – 2 tahun setelah
kejang terakhir, kemudian dihentikan secara bertahap selama 1 – 2 bulan. Pemberian
profilaksis terus menerus hanya berguna untuk mencegah berulangnya kejang demam
berat, tetapi tidak dapat mencegah timbulnya epilepsi di kemudian hari.
Pemberian fenobarbital 4 – 5 mg/kg BB perhari dibagi 2 dosis dengan kadar
sebesar 16 mg/mL dalam darah menunjukkan hasil yang bermakna untuk mencegah
berulangnya kejang demam. Efek samping fenobarbital ialah iritabel, hiperaktif,
pemarah dan agresif ditemukan pada 30–50 % kasus. Efek samping fenobarbital dapat
dikurangi dengan menurunkan dosis.
Obat lain yang dapat digunakan adalah asam valproat yang memiliki khasiat sama
dibandingkan dengan fenobarbital. Ngwane meneliti kejadian kejang berulang sebesar
5,5 % pada kelompok yang diobati dengan asam valproat dan 33 % pada kelompok
25

tanpa pengobatan dengan asam valproat. Dosis asam valproat adalah 15 – 40 mg/kg
BB perhari dibagi 2 dosis. Efek samping yang ditemukan adalah hepatotoksik, tremor
dan alopesia.
Fenitoin dan karbamazepin memiliki efek profilaksis terus menerus, dosis antara 4
– 8 mg/kgBB/hari dibagi dalam 2-3 dosis. Millichap merekomendasikan beberapa hal
dalam upaya mencegah dan menghadapi kejang demam :
• Orang tua atau pengasuh anak harus diberi cukup informasi mengenai penanganan
demam dan kejang.
• Profilaksis intermittent dilakukan dengan memberikan diazepam dosis 0,5 mg/kg
BB perhari, per oral pada saat anak menderita demam. Sebagai alternatif dapat
diberikan profilaksis terus menerus dengan fenobarbital.
• Memberikan diazepam per rektal bila terjadi kejang.
•Pemberian fenobarbital profilaksis dilakukan atas indikasi, pemberian sebaiknya
dibatasi sampai 6 – 12 bulan kejang tidak berulang lagi dan kadar fenoborbital dalam
darah dipantau tiap 6 minggu – 3 bulan, juga dipantau keadaan tingkah laku dan
psikologis anak.
J. KOMPLIKASI
Perkembangan mental dan neurologis akan terganggu pada sebagian kecil
penderita, hal ini terjadi pada penderita dengan kejang yang lama dan berulang, baik
umum atau fokal. Gangguan intelektual (penurunan IQ) dan gangguan belajar jarang
terjadi, apabila terjadi dikarenakan kejang demam yang berlangsung lama dan
mengalami komplikasi. Risiko retardasi mental menjadi 5 kali lebih besar apabila
kejang demam diikuti dengan terulangnya kejang tanpa demam. 95-98 % dari anak-
anak yang pernah mengalami kejang demam, tidak berlanjut menjadi epilepsi. Tetapi
beberapa anak memiliki resiko tinggi menderita epilepsi, jika:
- Kejang demam berlangsung lama.- Kejang hanya mengenai bagian tubuh tertentu. - Kejang demam yang berulang dalam waktu 24 jam.- Anak menderita cerebral palsy, gangguan pertumbuhan atau kelainan saraf lainnya.
K. PROGNOSIS
26

Dengan penanggulangan cepat dan tepat, prognosisnya baik dan tidak
menyebabkan kematian. Kemungkinan bangkitan kejang: sekitar 25-50% yang
umumnya terjadi pada 6 bulan pertama. Pada anak berumur kurang dari 13 tahun,
terulangnya kejang pada anak perempuan 50 %, laki – laki 33 %. Pada anak beumur
antara 14 bulan dan 3 tahun dengan riwayat keluarga adanya kejang, kemungkinan
bangkitan 50 % sedang tanpa riwayat keluarga kejang 25 %.
L. IMUNISASI DAN KEJANG DEMAM
Walaupun imunisasi dapat menimbulkan demam, namun imunisasi jarang diikuti
kejang demam. Suatu penelitian yang dilakukan memperlihatkan risiko kejang demam
pada beberapa jenis imunisasi sebagai berikut :
1. DTP : 6-9 per 100.000 imunisasi. Risiko ini tinggi pada hari imunisasi, dan
menurun setelahnya ( 3x dosis @0,4 ml IM pada usia 2,3,dan 4 bulan)
2. MMR : 25-34 per 100.000 imunisasi. Risiko meningkat pada hari 8-14 setelah
imunisasi (dosis tunggal 0,5 ml IM/SC dalam).
Kejang demam pasca imunisasi tidak memiliki kecenderungan berulang yang
lebih besar daripada kejang demam pada umumnya. Dan kejang demam pasca
imunisasi kemungkinan besar tidak akan berulang pada imunisasi berikutnya. Jadi
kejang demam bukan merupakan kontra indikasi imunisasi.
27

II. DIARE CAIR AKUT
A. DEFINISI
Menurut WHO (1999) secara klinis diare didefinisikan defekasi (buang air besar)
lebih dari biasanya/lebih dari tiga kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten
tinja (menjadi cair) dengan atau tanpa darah. Secara klinik dibedakan tiga macam
sindroma diare yaitu diare cair akut, disentri, dan diare persisten. Sedangkan menurut
menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya
perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan
bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari.
Sedangkan American Academy of Pediatrics (AAP) mendefinisikan diare dengan
karakteristik peningkatan frekuensi dan/atau perubahan konsistensi, dapat disertai
atau tanpa gejala dan tanda seperti mual, muntah, demam atau sakit perut yang
berlangsung selama 3 – 7 hari.
Diare akut diberi batasan sebagai meningkatnya kekerapan, bertambah cairan,
atau bertambah banyaknya tinja yang dikeluarkan, akan tetapi hal itu sangat relatif
terhadap kebiasaan yang ada pada penderita dan berlangsung tidak lebih dari satu
minggu. Apabila diare berlangsung antara satu sampai dua minggu maka dikatakan
diare yang berkepanjangan.
B. EPIDEMIOLOGI
Diare merupakan salah satu penyakit paling sering menyerang anak di seluruh
dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan angka kejadian di negara berkembang
berkisar 3,5-7 episode per anak pertahun dalam 2 tahun pertama kehidupan dan 2-5
episode per anak per tahun dalam 5 tahun pertama kehidupan. Faktor resiko terjadinya
diare antara lain:
a. Tidak memberikan ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama kehidupan
b. Menggunakan air minum yang tercemar oleh bakteri yang berasal dari tinja.
c. Tidak mencuci tangan sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja atau
sebelum memasak makanan.
C. KLASIFIKASI
Diare secara garis besar dibagi atas radang dan non radang. Diare radang dibagi
lagi atas infeksi dan non infeksi.
28

D. ETIOLOGI
Etiologi diare dapat dibagi dalam beberapa faktor yaitu:
a. Faktor infeksi
1) Infeksi enteral
- Infeksi bakteri : Vibrio, E.coli, Salmonella, Shigella, campylobacter,
Yersinia, Aeromonas, dan sebagainya.
- Infeksi Virus : Enterovirus, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus dan
lain-lain.
- Infeksi parasit : cacing (ascaris, triciuris,dll.) protozoa, dan jamur.
2) Infeksi parenteral yaitu ineksi dibagian tubuh lain diluar alat
pencernaan, seperti OMA, tonsilofaringitis, bronkopneumonia,
ensefalitis, dan sebagainya.
b. Faktor malabsorbsi (malabsorbsi karbohidrat, malabsorbsi lemak,
malabsorbsi protein)
c. Faktor makanan: makanan basi, beracun dan alergi terhadap makanan.
d. Faktor psikologis : rasa takut dan cemas
E. PATOGENESIS
Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare ialah
a. Gangguan osmotik: terjadi akibat adanya makanan atau zat yang tidak
dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus
meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga
usus sehingga timbul diare.
b. Gangguan sekresi: terjadi akibat ransangan tertentu pada dinding usus akan
terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit kedalam rongga usus dan
selanjutnya timbul diare.
c. Gangguan motilitas usus: terjadi karena hiperperistaltik akan
mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan
sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan
mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat
menimbulkan diare.
F. PATOFISIOLOGI
Ada beberapa mekanisme patofisiologis yang terjadi, sesuai dengan penyebab
diare. Virus dapat secara langsung merusak vili usus halus sehingga mengurangi luas
permukaan usus halus dan mempengaruhi mekanisme enzimatik yang mengakibatkan
29

terhambatnya perkembangan normal vili enterocytes dari usus kecil dan perubahan
dalam struktur dan fungsi epitel. Perubahan ini menyebabkan malabsorbsi dan
motilitas abnormal dari usus selama infeksi rotavirus.
Bakteri mengakibatkan diare melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Bakteri
non invasive (vibrio cholera, E.coli patogen) masuk dan dapat melekat pada usus,
berkembang baik disitu, dan kemudian akan mengeluarkan enzim mucinase
(mencairkan lapisan lendir), kemudian bakteri akan masuk ke membran, dan
mengeluarkan sub unit A dan B, lalu mengeluarkan cAMP yang akan merangsang
sekresi cairan usus dan menghambat absorpsi tanpa menimbulkan kerusakan sel
epitel. Tekanan usus akan meningkat, dinding usus teregang, kemudian terjadilah
diare
Bakteri invasive (salmonella spp, shigella sp, E.coli invasive, campylobacter)
mengakibatkan ulserasi mukosa dan pembentukan abses yang diikuti oleh respon
inflamasi. Toksin bakteri dapat mempengaruhi proses selular baik di dalam usus
maupun di dalam usus. Enterotoksin Escherichia coli yang tahan panas akan
mengaktifkan adenilat siklase, sedangkan toksin yang tidak tahan panas mengaktifkan
guanilat siklase. E.coli enterohemoragik dan Shigella menghasilkan verotoksin yang
menyebabkan kelainan sistemik seperti kejang dan sindrom hemolitik uremik.
G. GEJALA KLINIS
Mula-mula bayi/anak menjadi cengeng, gelisah, suhu badan mungkin meningkat,
nafsu makan berkurang atau tidak ada kemudian timbul diare. Karena seringnya
defekasi, anus dan sekitarnya lecet karena tinja makin lama makin menjadi asam
akibat banyaknya asam laktat, yang terjadi dari pemecahan laktosa yang tidak dapat
diabsorpsi oleh usus. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare. Bila
penderita telah banyak kehilangan air dan elektrolit terjadilah gejala dehidrasi. Berat
badan turun, pada bayi ubun-ubun besar cekung, tonus dan turgor kulit berkurang,
selaput lendir mulut dan bibir terlihat kering.
H. DEHIDRASI
Pembagian dehidrasi menurut Modul Pelatihan Diare. UKK Gastro-Hepatologi
IDAI. 2009
Kategori Tanda dan gejala
30

Dehidrasi Berat
REHIDRASI PLAN C
Dua atau lebih tanda berikut:
Letargi atau penurunan kesadaran
Mata cowong
Tidak bisa minum atau malas minum
Cubitan perut kembali dengan sangat
lambat (≥ 2 detik)
Dehidrasi Tak Berat (Ringan-
Sedang)
REHIDRASI PLAN B
Dua atau lebih tanda berikut:
Gelisah
Mata Cowong
Kehausan atau sangat haus
Cubitan kulit perut kembali dengan
lambat
Tanpa Dehidrasi
REHIDRASI PLAN A
Tidak ada tanda gejala yang cukup
untuk mengelompokkan dalam
dehidrasi
berat atau tidak berat
Ada tiga macam dehidrasi :
- Dehidrasi isotonik Ini adalah dehidrasi yang sering terjadi karena diare. Hal
ini terjadi bila kehilangan air dan natrium dalam proporsi yang sama
dengan keadaan normal dan ditemui dalam cairan ekstraseluler.
- Dehidrasi Hipertonik Beberapa anak yang diare, terutama bayi sering
menderita dehidrasi hipernatremik. Pada keadaan ini didapatkan
kekurangan cairan dan kelebihan natrium. Bila dibandingkan dengan
proporsi yang biasa ditemukan dalam cairan ekstraseluler dan darah. Ini
biasanya akibat dari pemasukan cairan hipertonik pada saat diare yang tidak
di absopsi secara efisien dan pemasukan air yang tidak cukup. 3.
- Dehidrasi Hipotonik Anak dengan diare yang minum air dalam jumlah
besar atau yang mendapat infus 5 % glukosa dalam air, mungkin bisa
menderita hiponatremik. Hal ini terjadi karena air diabsopsi dari usus
sementara kehilangan garam (NaCl) tetap berlangsung dan menyebabkan
kekurangan natrium dan kelebihan air.
31

I. PENATALAKSANAAN
Terdapat lima lintas tatalaksana, yaitu :
a. Rehidrasi
a.i Rehidrasi Plan A
Tidak perlu dirujuk
Prinsip rehidrasi Plan A:
1.Berikan cairan tambahan
2.Teruskan pemberikan makan
3.Berikan suplemen seng (Zn)
4.Sarankan kepada ibu kapan harus kembali :
-BAB menjadi lebih sering
-Muntah berulang
-Rasa haus meningkat
-Tidak dapat makan serta minum seperti biasanya
a.ii Rehidrasi Plan B
Rehidrasi pada dehidrasi ringan dan sedang dapat dilakukan dengan pemberian oral
sesuai dengan defisit yang terjadi namun jika gagal dapat diberikan secara intravena
sebanyak : 75 ml/kg bb/3jam. Pemberian cairan oral dapat dilakukan setelah anak
dapat minum sebanyak 5ml/kgbb/jam. Biasanya dapat dilakukan setelah 3-4 jam pada
bayi dan 1-2 jam pada anak . Penggantian cairan bila masih ada diare atau muntah
dapat diberikan sebanyak 10ml/kgbb setiap diare atau muntah.
Secara ringkas kelompok Ahli gastroenterologi dunia memberikan 9 pilar yang
perlu diperhatikan dalam penatalaksanaan diare akut dehidrasi ringan sedang pada
anak, yaitu :
1. Menggunakan CRO ( Cairan rehidrasi oral )
2. Cairan hipotonik
3. Rehidrasi oral cepat 3 – 4 jam
4. Realiminasi cepat dengan makanan normal
5. Tidak dibenarkan memberikan susu formula khusus
6. Tidak dibenarkan memberikan susu yang diencerkan
7. ASI diteruskan
8. Suplemen dnegan CRO ( CRO rumatan )
9. Anti diare tidak diperlukan
32

a.iii Rehidrasi Plan C
Penderita dengan dehidrasi berat, yaitu dehidrasi lebih dari 10% untuk bayi dan
anak dan menunjukkan gangguan tanda-tanda vital tubuh ( somnolen-koma,
pernafasan Kussmaul, gangguan dinamik sirkulasi ) memerlukan pemberian cairan
elektrolit parenteral. Penggantian cairan parenteral menurut panduan WHO diberikan
sebagai berikut:
Usia <12 bln: 30ml/kgbb/1jam, selanjutnya 70ml/kgbb/5jam
Usia >12 bln: 30ml/kgbb/1/2-1jam, selanjutnya 70ml/kgbb/2-2½ jam
Walaupun pada diare terapi cairan parenteral tidak cukup bagi kebutuhan penderita
akan kalori, namun hal ini tidaklah menjadi masalah besar karena hanya menyangkut
waktu yang pendek. Apabila penderita telah kembali diberikan diet sebagaimana
biasanya . Segala kekurangan tubuh akan karbohidrat, lemak dan protein akan segera
dapat dipenuhi. Itulah sebabnya mengapa pada pemberian terapi cairan diusahakan
agar penderita bila memungkinkan cepat mendapatkan makanan / minuman sebagai
biasanya bahkan pada dehidrasi ringan sedang yang tidak memerlukan terapi cairan
parenteral makan dan minum tetap dapat dilanjutkan.
b. Dukungan nutrisi
Makanan tetap diteruskan sesuai usia anak dengan menu yang sama pada aktu
anak sehat sebagai pengganti nutrisi yang hilang, serta mencegah tidak terjadi gizi
buruk. ASI tetap diberikan pada diare cair akut (maupun pada diare akut berdarah)
dan diberikan dengan frekuensi lebih sering dari biasanya.
c. Suplementasi Zinc
Efek zinc antara lain sebagai berikut :
- Zinc merupakan kofaktor enzim superoxide dismutase (SOD). SOD
akan merubah anion superoksida (merupakan radikal bebas hasil
sampingan dari proses sintesis ATP yang sangat kuat dan dapat merusak
semua struktur dalam sel) menjadi H2O2, yang selanjutnya diubah
menjadi H2O dan O2 oleh enzim katalase. Jadi SOD sangat berperan
dalam menjaga integritas epitel usus.
- Zinc berperan sebagai anti-oksidan, ‘berkompetisi’ dengan tembaga (Cu)
dan besi (Fe) yang dapat menimbulkan radikal bebas.
33

- Zinc menghambat sintesis Nitric Oxide (NO). Dengan pemberian zinc,
diharapkan NO tidak disintesis secara berlebihan sehingga tidak terjadi
kerusaan jaringan dan tidak terjadi hipersekresi.
- Zinc berperan dalam penguatan sistem imun.
- Zinc berperan dalam menjaga keutuhan epitel usus, berperan sebagai
kofaktor berbagai faktor transkripsi sehingga transkripsi dalam sel usus
dapat terjaga.
d. Antibiotik selektif
Antibiotik tidak diberikan pada kasus diare cair akut, kecuali dengan
indikasi yaitu pada diare berdarah dan kolera.
e. Edukasi orang tua
34

BAB III
PEMBAHASAN
Pada pasien ini didiagnosis kejang demam sederhana karena:
1. Durasi kejang 30 detik (kejang <15 menit)
2. Kejang 1x24 jam (tidak berulang dalam 24 jam)
3. Kejang baru pertama kali (Frekuensi bangkitan kejang dalam 1 tahun tidak
lebih dari 4x)
4. Kejang seluruh tubuh, kedua tangan kaku (Kejang bersifat generalized dan
klonik)
Hal ini sesuai dengan kriteria kejang demam sederhana menurut IDAI tahun 2006.
Pemeriksaan fisik setelah kejang didapatkan pupil isokor, BBU datar, reflek
cahaya (+) (Pemeriksaan neurologis sesudah kejang normal)
Setelah kejang, keluarga mengatakan anak menangis, Saat dibawa ke IGD kondisi
anak tidak kejang, dan pemeriksaan meningeal sign hasilnya negatif. (Kesadaran
anak setelah kejang adalah kompos mentis, tanpa kelainan neurologis yang
berat )
Kejang disertai dengan demam sejak pukul 10.30. Saat datang ke IGD, suhu anak
38°C, demam belum turun. (Kejang diawali oleh demam. Kejang timbul < 16
jam pertama setelah timbulnya demam)
Pasien ini juga didiagnosis diare cair akut tanpa dehidrasi karena:
1. Frekuensi BAB >3x dalam sehari, dengan konsistensi cair
Ini sesuai dengan definisi diare menurut DEPKES tahun 2005, yakni adanya
perubahan dalam bentuk dan konsistensi tinja dari lembek sampai cair, disertai
dengan BAB lebih dari 3 kali dalam sehari.
2. Tidak cukup terdapat tanda-tanda dehidrasi ringan-sedang dan berat, pada pasien
ini mata tidak cowong, turgor kulit masih baik, tidak tampak gelisah, masih mau
minum, tidak terlihat lahap saat minum, dan tidak malas minum, mukosa bibir dan
mulut basah, air mata (+).
3. Diare tanpa lendir dan darah, menunjukkan diare cair akut, bukan disentri form,
anak juga tidak tampak kesakitan saat BAB, karena pada diare disentri form
terdapat nyeri perut saat BAB.
35

4. Dari hasil anamnesis juga didapatkan bahwa ibu pasien tidak cebok
menggunakan sabun setelah BAB, lingkungan rumah didekat sungai, mencuci
pakaian dan BAB di sungai, anak kadang juga mandi di sungai. Hal ini
memungkinkan penyebab diare dikarenakan faktor infeksi. Diare cair akut disertai
demam dan limfositosis pada pemeriksaan darah lengkap, menunjukkan adanya
infeksi teutama virus. Lebih dari 50% diare cair akut di negara berkembang
disebabkan oleh rotavirus.
Terapi yang diberikan yaitu :
1. Infus Kaen 3B 8 tpm
Larutan rumatan nasional untuk memenuhi kebutuhan harian air dan elektrolit
dengan kandungan kalium cukup untuk mengganti ekskresi harian, pada keadaan
asupan oral terbatas. Pada pasien ini masih mau minum, tetapi hanya sebentar-
sebentar, dikhawatirkan asupan oral tidak memenuhi kebutuhan cairan yang
dibutuhkan sehingga bisa terjadi dehidrasi.
2. Injeksi cefotaxim 3x400 mg
Menurut WHO Guideline on the management of acute diarrhea in children tahun
2011, pemberian antibiotik hanya diindikasikan untuk disentri (shigella), cholera,
diare dengan infeksi lain seperti ISK, pneumonia, dll, salmonella,
immunocompromised, dan diare pada malnutrisi. Jadi pada kasus ini sebaiknya
tidak diberikan antibiotik.
3. Diazepam 1 mg per oral bila suhu >38,5 C
Pemberian diazepam 1 mg per oral merupakan terapi intermittent untuk kejang
demam sederhana, pemberian diazepam sebagai terapi intermittent sesuai dengan
febrile seizure guideline treatment dari medscape, merekomendasikan untuk
pemberian intermittent diazepam saat suhu diatas 38,5 C. Berdasarkan penelitian
dari AAP, pemberian diazepam secara intermittent dapat menurunkan kekambuhan
kejang demam sederhana berulang sebanyak 11%.
4. Zink 1x20 mg peroral
Zinc berperan dalam menjaga keutuhan epitel usus, berperan sebagai kofaktor
berbagai faktor transkripsi sehingga transkripsi dalam sel usus dapat terjaga.
5. Paracetamol sirup 1 cth
Pemberian paracetamol bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh anak saat suhu
lebih dari 37,5 C, sehingga kemungkinan terjadinya kejang saat demam dapat
dicegah.
36

BAB IV
KESIMPULAN
1. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu
tubuh (suhu rektal di atas 38oC) tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat atau
gangguan elektrolit akut, terjadi pada 2 – 4 % anak antara umur 6 bulan – 5
tahun (menurut consensus statement on febrile seizures).
2. Kejang demam timbul karena demam yang mendadak tinggi pada anak. Selain
faktor genetik, kejang demam juga berhubungan dengan beberapa penyakit
antara lain infeksi saluruan napas atas, otitis media, radang paru-paru, radang
usus dan lambung, infeksi saluran kencing, keracunan, meningitis dan
ensefalitis, roseola (oleh virus herpes manusia 6), dan disentri karena shigella.
3. Unit Kerja Koordinasi Neurologi IDAI 2006 membuat klasifikasi kejang
demam pada anak menjadi : Kejang Demam Sederhana dan Kejang Demam Kompleks.
4. Tujuan pengobatan kejang demam pada anak adalah untuk : Mencegah kejang
demam berulang, mencegah status epilepsy, mencegah epilepsi dan / atau
mental retardasi, dan normalisasi kehidupan anak dan keluarga.
5. Pengobatan kejang demam terdiri dari : a. Pengobatan Fase Akut dengan
diazepam per rectal 5 mg, b. Mencari dan mengobati penyebab infeksi fokal,
c. Pengobatan profilaksis terhadap kejang demam berulang
6. Penyebab demam pada kasus ini adalah infeksi pada saluran pencernaan yaitu
diare cair akut.
7. Diare adalah diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya
perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair
dan bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih
dalam sehari.
37

8. Hal yang penting diperhatikan dari diare adalah adanya tanda – tanda
dehidrasi, dibagi menjadi tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan-sedang, dehidrasi
berat.
9. Terdapat lima tatalaksana dalam penanganan diare, yaitu : rehidrasi, dukungan
nutrisi, suplementasi zinc, antibiotic selektif, dan edukasi orang tua.
38

DAFTAR PUSTAKA
- Deliana, Melda. 2002. Tatalaksana Kejang Demam pada Anak. Sari Pediatri, Vol.
4, No. 2, September 2002: 59 – 62
- Departemen kesehatan RI Profil Kesehatan Indonesia 2001. Jakarta 2002.
- Dwipoerwantoro PG.Pengembangan rehidrasi perenteral pada tatalaksana diare
akut dalam kumpulan makalah Kongres Nasional II BKGAI Juli 2003.
- Haslam Robert H. A. Sistem Saraf, dalam Ilmu Kesehatan Anak Nelson, Vol.3,
Edisi 15. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 2000; XXVII; 2059-2060.
- Hendarto S.K. Kejang Demam. Subbagian Saraf Anak, Bagian Ilmu Kesehatan
Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM, Jakarta. Cermin Dunia
Kedokteran No.27. 2004: 6-8
- Ismael, Sofyan Prof.Dr.SpA(K)., dkk. 2005. Unit Kerja Koordinasi Neurologi
Ikatan Dokter Anak Indonesia, Konsensus Penanganan Kejang Demam. Ikatan
Dokter Anak Indonesia.
- Juffire M, Mulyani NS. 2009. Modul Pelatihan Diare. UKK Gastro-Hepatologi
IDAI.
- M.Bambang Edi, dr, Sp(A). 2012. Study Guide, Panduan Kepaniteraan Klinik
Ilmu Kesehatan Anak. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit, Pedoman Bagi Rumah Sakit Rujukan
Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota. 2009. World Health Organization, Country
Office for Indonesia, Jakarta.
- Pusponegoro, D. H., dkk, 2004, Standar Pelayanan Medis Kesehatan Anak, Edisi
1. IDAI, Jakarta.
- Shann F. 2006. Drug Doses 13 edition.
39