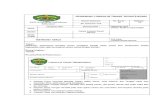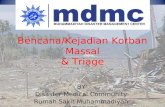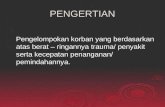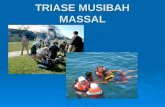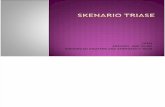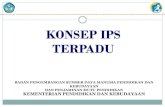BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Triase
Transcript of BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Triase

8
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Triase
2.1.1 Definisi Triase
Triase berasal dari bahasa Prancis trier bahasa Inggris triage dan
diturunkan dalam bahasa Indonesia triase yang berarti sortir yaitu
proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau pe
nyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat. Kini istilah
tersebut lazim digunakan untuk menggambarkan suatu konsep
pengkajian yang cepat dan berfokus dengan suatu cara yang
memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta
fasilitas yang paling efisien terhadap 100 juta orang yang
memerlukan perawatan di IGD setiap tahunnya (Andara, 2019).
Triase adalah suatu tindakan pemilihan pasien berdasarkan pada
tingkat kegawatannya, keparahanya dan cidera yang diprioritaskan
apakah ada atau tidaknya gangguan seperti Airway (A), Breathing
(B), dan Circulation (C) dengan mempertimbangkan sumber daya
manusia, sarana dan probabilitas hidup pasien (Kartikawati, 2013).
Dari pengertian tersebut maka triase dapat didefinisikan sebagai
upaya pengelompokkan pasien secara cepat dengan memperhatikan
gejala berupa berat atau ringannya cedera yang dialami pasien ada
atau tidaknya gangguan Airway, Breathing, dan Circulation.
2.1.2 Tujuan Triase
Tujuan Triase adalah memberikan petolongan secara cepat, tepat
terutama pada korban dalam keadaan kritis atau emergensi yang
memerlukan tindakan segera sehingga nyawa korban dapat
diselamatkan (Garbez, et all. 2011).


9
Tujuan triase menurut Nusdin (2020) antara lain :
2.1.2.1 Mengidentifikasi kondisi pasien atau korban yang
mengancam nyawa.
2.1.2.2 Mengidentifikasi cepat pasien yang memerlukan stabilisasi
segera.
2.1.2.3 Memprioritaskan pasien menurut kondisi keakurat yang
dialami pasien
2.1.2.4 Mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kecacatan.
2.1.2.5 Mengidentifikasi pasien yang hanyar dapat diselamatkan
dengan pembedahan.
2.1.2.6 Bertindak dengan cepat dan waktu yang tepat serta
melakukan yang terbaik untuk pasien.
2.1.3 Prinsip dalam pelaksanaan triase
Menurut Andara, (2019) prinsip – prinsip triase terbagi menjadi 6
yaitu:
2.1.3.1 Triase seharusnya dilakukan segera dan tepat waktu
kemampuan berespon dengan cepat terhadap kemungkinan
penyakit yang mengancam kehidupan atau injuri adalah hal
yang terpenting di departemen kegawatdaruratan.
2.1.3.2 Pengkajian seharusnya adekuat dan akurat
Intinya, ketelitian dan keakuratan adalah elemen yang
terpenting dalam proses interview.
2.1.3.3 Keputusan dibuat berdasarkan pengkajian
Keselamatan dan perawatan pasien yang efektif hanya dapat
direncanakan bila terdapat informasi yang adekuat serta data
yang akurat.
2.1.3.4 Melakukan intervensi berdasarkan keakutan dari kondisi
Tanggung jawab utama seorang perawat triase adalah
mengkaji secara akurat seorang pasien dan menetapkan
prioritas tindakan untuk pasien tersebut. Hal tersebut

10
termasuk intervensi terapeutik, prosedur diagnostic dan tugas
terhadap suatu tempat yang dapat diterima untuk suatu
pengobatan.
2.1.3.5 Tercapainya kepuasan pasien
a. Perawat triase seharusnya memenuhi semua yang ada di
atas saat menetapkan hasil secara serempak dengan pasien.
b. Perawat membantu dalam menghindari keterlambatan
penanganan yang dapat menyebabkan keterpurukan status
kesehatan pada seseorang yang sakit dengan keadaan
kritis.
c. Perawat memberikan dukungan emosional kepada pasien
dan keluarga atau temannya.
2.1.3.6 Pengambilan keputusan dalam proses triage dilakukan
berdasarkan :
a. Ancaman jiwa mematikan dalam hitungan menit.
b. Dapat mati dalam hitungan jam.
c. Trauma ringan.
d. Sudah meninggal
2.1.4 Klasifikasi Triase
Klasifikasi triase dibagi menjadi beberapa level tingkat keperawatan.
Tingkat level keperawatan didasarkan pada tingkat kegawatan,
tingkat prioritas, tingkat kedaruratan, tingkat keakutan, dan lokasi
kejadian. Berikut 5 klasifikasi triase menurut Mardalena (2016):
2.1.4.1 Klasifikasi Kegawatan Triase
Berdasarkan (Oman, 2008 dalam Andara safery wijaya,
2019), pengambilan keputusan triage di dasarkan pada
keluhan utama, riwayat medis, dan data objektif yang
mencakup keadaan umum pasien serta hasil pengkajian fisik
yang terfokus. Penentuan triase didasarkan pada kebutuhan
fisik, tumbuh kembang dan psikososial selain pada faktor-
faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan serta

11
alur pasien lewat sistem pelayanan kedaruratan. Hal - hal
yang harus dipertimbangkan mencakup setiap gejala ringan
yang cenderung berulang atau meningkat keparahannya.
Beberapa hal yang mendasari klasifikasi pasien dalam sistem
triage adalah kondisi klien yang meliputi :
a. Gawat
Suatu keadaan yang mengancam nyawa dan kecacatan
yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat.
b. Darurat
Suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa tapi
memerlukan penanganan cepat dan tepat seperti
kegawatan.
c. Gawat darurat
Suatu keadaan yang mengancam jiwa disebabkan oleh
gangguan ABC (Airway / jalan nafas, Breathing /
pernafasan, Circulation / sirkulasi), jika tidak ditolong
segera maka dapat meninggal / cacat .
2.1.4.2 Klasifikasi Tingkat Prioritas
Klasifikasi triase dari tingkat keutamaan atau prioritas, di
bagi menjadi 4 warna. Klasifikasi prioritas ditandai dengan
beberapa tanda warna. Berikut beberapa warna yang sering
digunakan untuk triase (Mardalena, 2016):
a. Biru
Warna biru digunakan untuk menandai pasien yang harus
segera atau ditangani dan tingkat prioritas pertama. Warna
biru menandakan bahwa pasien dalam keadaan
mengancam jiwa yang menyerang bagian vital. Pasien
yang bertanda biru, jika tidak segera ditangani dapat
menyebabkan kematian. Berikut termasuk prioritas
pertama (warna biru) diantaranya adalah sumbatan, henti

12
nafas (frekuensi nafas <10x/menit), sianosis, henti
jantung, nadi tidak teraba, pucat, akral dingin, dan GCS
<8.
b. Merah
Warna merah digunakan untuk menandai pasien yang
harus segera atau ditangani dan tingkat prioritas pertama
setelah triase biru.Warna merah menandakan bahwa
pasien dalam keadaan mengancam jiwa, prioritas pertama
(warna merah) diantaranya adalah frekuensi
nafas>32x/menit, suara nafas mengi, nadi terasa lemah,
nadi <50x/menit>150x/menit, pucat, akral dingin, CRT<2
detik, dan GCS 9-12.
c. Kuning
Pasein yang diberi tanda kuning juga berbahaya dan harus
segera atau cepat untuk ditangani. Akan tetapi, tanda
kuning menjadi tingkat prioritas kedua setelah tanda
merah. Dampak jika tidak segera ditangani, akan
mengancam fungsi vital organ tubuh bahkan mengancam
nyawa. Prioritas pertama (warna kuning) diantaranya
adalah frekuensi nafas >24- 32 x/ menit, suara nafas
mengi, tekanan darah sistol > 160mmHg, diastol
>100mmHg dan GCS>12.
Contoh pasien yang terkena luka bakar tingkat II dan III
kurang dari 25% mengalami trauma thorak, trauma bola
mata, dan laserasi luas. Adapun yang termasuk prioritas
kedua, di antaranya yaitu luka bakar pada daerah vital,
seperti kemaluan, luka pada kepala atau subdural hematom
yang ditandai dengan muntah dan perdarahan (seperti di
telinga, mulut dan hidung).

13
d. Hijau
Hijau merupakan tingkat prioritas ketiga. Warna hijau
mengisyaratkan bahwa pasien hanya perlu penanganan
dan perawatan biasa. Pasien tidak dalam kondisi gawat
darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya.
Pasien yang diberi prioritas warna hijau menandakan
bahwa pasien hanya mengalami luka ringan atau sakit
ringan. Prioritas pertama (warna hijau) diantaranya adalah
frekuensi nafas 16-29x/menit, nadi 8-120x/menit, tekanan
darah sistol 120-160 mmHg, diastole 80-100 mmHg dan
GSC 15. Contoh luka superfisial. Penyakit atau luka yang
masuk ke prioritas hijau adalah fraktur ringan disertai
perdarahan, benturan ringan atau laserasi, histeris, dan
luka bakar ringan.
2.1.4.3 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kedaruratan Triase
Menurut Kartikawati (2011) dalam pemberian label pada
pasien dapat diklasifikasikan menjadi berikut:
a. Korban kritis/immediate diberi label merah/kegawatan
yang mengancam nyawa (prioritas 1)
b. Delayed/tertunda diberi label kuning/kegawatan yang
tidak mengancam nyawa dalam waktu dekat (prioritas 2 )
c. Korban terluka yang masih dapat berjalan diberi lebel
hijau atau tidak terdapat kegawatanya atau penangananya
dapat ditunda (prioritas 3). Ada dua cara yang bisa
dilakukan. Pertama secara validitas, yaitu merupakan
tingkat akurasi sistem kedaruratan. Kedua, secara rebilitas
yaitu perawat yang menangani pasien sama dan
menentukan tingkat kedaruratan yang sama pula. Kedua

14
cara tersebut sering digunakan untuk menganalisis dan
menentukan kebijakan untuk pasien yang dirawat di IGD.
2.1.4.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Keakutan
Menurut Iyer (2004) dalam Mardalena (2016), menyatakan
pentingnya petunjuk yang dikuasai oleh perawat triage.
Perawat dituntut mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk
klasifikasi prioritas tinggi seperti perdarahan aktif, nyeri
hebat, gangguan emosi, stupor, diaphoresis, dispnea saat
istirahat, tanda-tanda vital di luar batas normal dan sianosis.
Klasifikasi triage berdasarkan tingkat keakutan dibagi ke 5
tingkatan, sebagai berikut (Mardalena, 2016):
a. Kelas I
Kelas satu meliputi pasien yang masih mampu menunggu
lama tanpa menyebabkan bahaya dan tidak mengancam
nyawa. Contohnya seperti pasien mengalami memar
minor.
b. Kelas II
Pasien termasuk kelas dua adalah penyakit ringan, yang
tidak membahayakan diri pasien. Contohnya seperti flu,
demam biasa, atau sakit gigi.
c. Kelas III
Pasien yang berada di kelas tiga, pasien berada dalam
kondisi semakin mendesak. Pasien tidak mampu
menunggu lebih lama. Contohnya seperti pasien yang
mengalami otitis media.
d. Kelas IV
Adapun pasien yang tidak mampu menahak kurang dari
dua jam dikategorikan kelas IV. Pasien hanya mampu
bertahan selama pengobatan, sebelum ditindaklanjuti.
Pasien kelas IV ini termasuk urgen dan mendasar.

15
Contohnya seperti penderita asma, fraktur panggul dan
laserasi berat.
e. Kelas V
Pasien yang berada di kelas V adalah pasien gawat
darurat. Apabila pasien diobati terlambat, dapat
menyebabkan kematian. Contohnya seperti syok, henti
jantung, dan gagal jantung.
2.1.4.5 Klasifikasi Berdasarkan Lokasi Kejadian
Triage yang digunakan dalam rumah sakit meliputi beberapa
poin sebagai berikut (Mardalena, 2016):
a. Triage Pre-Hospital
Triage Pre-Hospital merupakan tindakan penyelamatan
pasien yang sedang mengalami gangguan medis atau
trauma. Triage ini juga mampu mengurangi resiko cedera
atau luka yang lebih parah. Triage pre-hospital digunakan
sebagai upaya awal perawat untuk menggali data pasien.
Triage pre-hospital memiliki keterbatasan staf medis.
contohnya dalam satu ambulans hanya terdapat dua
perawat dan kondisi pasien yang membutuhkan banyak
alat dan obat-obatan yang lebih lengkap, tindakan perawat
yang cepat tanggap dengan keterbatasan alat dan obat
selama di ambulans inilah yang disebut dengan istilah pre-
hospital care.
Contohnya pada saat kondisi bencana alam. Perawat tidak
boleh berhenti saat melakukan pengkajian kecuali untuk
mengamankan jalan napas dan menghentikan perdarahan
yang terjadi. Selain melakukan triage (pemilahan korban),
penolong lain akan melakukan follow up dan perawatan

16
jika diperlukan di lokasi. Apabila penolong lain sudah tiba
di lokasi kejadian, maka korban akan dilakukan re-triage
(dengan pemeriksaan yang lebih lengkap untuk mengenali
kegawatan yang mungkin terjadi), evaluasi lebih lanjut,
resusitasi, stabilisasi dan transportasi. Re-triage dilakukan
dnegan menggunakan pemasangan label Sistem yang
sudah mencantumkan identitas adna hasil pemeriksaan
terhadap korban. Menurut Mardalena (2016), dalam
penggolongan pasien juga di dilakukan teknik START
(Simple Triage and Rapid Treatment). Prinsip dari START
adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang
tersumbat dan perdarahan masif arteri. START dapat
dengan cepat dan akurat tidak boleh lebih dari 60 detik.
b. Triage In-Hospital
Menurut Thomson dan Dians (1992) dalam Mardalena
(2016), perawat bertanggung jawab menentukan prioritas
perawatan pasien. Ada tiga tipe dalam sistem triage in-
hospital, sebagai berikut:
1) Traffic Director/Triage Non-Nurse
Traffic Director disebut juga dengan triage non-nurse.
Perawat bukanlah bagian staf yang berlisensi. Selama
di lapangan perawat bertugas melakukan kajian visual
secara cepat dan tepat. Hal tersebut dilakukan dengan
menanyakan keluhan utama pasien. Tipe ini dilakukan
tidak berdasarkan standar dan tidak memakai
dokumentasi.
2) Spot Check Triage/Advance Triage
Spot Check Triage atau disebut dengan advance
triage merupakan kebalikan dari tipe pertama.

17
Perawat dan dokter harus sudah memiliki lisensi
untuk melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan
dengan cepat, seperti pengkajian latar belakang dan
evaluasi yang bersifat subjektif ataupun objektif.
3) Comprehensive Triage
Comprehensive Triage merupakan tipe yang
diterapkan bagi perawat yang tidak memiliki lisensi.
Perawat nantinya akan diberikan pelatihan dan
pengalaman triage. dalam pelatihan tersebut, perawat
juga diberi bekal tentang tes diagnostik, dokumentasi,
evaluasi ulang dari pasien, dan penatalaksanaan
spesifik. Penanganan triage in-hospital ada beberapa
macam seperti sistem ESI (Emergency Severity
Index), CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale)
dari Canada, MTS (Manchester Triage Scale) dari
Inggris, ATS (Australasia Triage Scale) dari
Australia, (Gilboy dkk. 2012).
a) ESI (Emergency Severity Index) atau Indeks
Keparahan Darurat adalah algoritma triase dengan
5 (lima) prioritas yang dikategorikan pasien gawat
darurat oleh perawat dengan mengevaluasi
keparahan pasien dan kebutuhan sumber daya.
Pada sistem Trigae ESI perawat triase hanya
menilai tingkat keparahan. Jika pasien tidak dalam
kriteria tingkat keparahan tergolong level 1 atau 2,
perawat triase akan mengevaluasi. ESI banyak
diterapkan di Asia, Australia dan Eropa, termasuk
rumah sakit di Indonesia. ESI terdiri 5 skala
prioritas, yaitu :

18
Tabel 2.1 Klasifikasi Triase
Kategori
ESI Keterangan
ESI 1 Apabila pasien memerlukan intervensi penyelamatan
jiwa
ESI 2 Apabila pasien tidak bisa menunggu karena resiko
tinggi, perubahan kesadaran akut , atau nyeri hebat
ESI 3 Apabila pasien memerlukan lebih satu sumber daya
ESI 4 Apabila pasien memerlukan sumberdaya lebih hanya
satu
ESI 5 Apabila pasien bisa menunggu karena resiko tidak
tinggi, tidak terjadi perubahan kesadaran akut atau nyeri
hebat
Sumber: Nicki Gilboy (2011) dan terrdapat dalam
Datusanantyo (2013)
(1) Prioritas 1 / ESI 1 (Label Biru )
Prioritas 1 adalah untuk pasien dengan kondisi yang
mengancam jiwa (impending life/limb threatening
problem) sehingga perlu tindakan penyelematan jiwa yang
segera. Pasien dengan level ESI 1 selalu datang ke ruang
gawat darurat dengan kondisi yang tidak stabil. Pasien
tersebut dapat meninggal bila penanganannya terlambat,
oleh karena itu respon dari tim IGD harus cepat. Parameter
prioritas 1 adalah semua gangguan signifikan pada ABCD.
Contohnya sebagai berikut : cardiac arrest, status
epileptikus, koma hipoglikemik dan lain-lain.
(2) Prioritas 2 / ESI 2 (Label Merah)
Prioritas 2 adalah untuk pasien dengan kondisi yang
berpotensi mengancam jiwa atau organ sehingga
membutuhkan pertolongan yang sifatnya segera dan tidak
dapat ditunda. Pada level ini, pasien masih tergolong
resiko tinggi dan penanganan harus dilakukan segera.
Sementara itu ESI tidak membatasi secara spesifik interval

19
waktu yang diperlukan. Parameter prioritas 2 adalah
pasien-pasien dengan haemodinamik atau ABC stabil
disertai penurunan kesadaran tapi tidak sampai koma
(GCS 8-12). Contohnya sebagai berikut : serangan asma,
penurunan kesadaran dan nyeri yang hebat, abdomen akut,
luka sengatan listrik dan lain-lain.
(3) Prioritas 3 / ESI 3 (Label Kuning)
Prioritas 3 adalah untuk pasien yang perlu evaluasi yang
mendalam dan pemeriksaan klinis yang menyeluruh.
Pasien label kuning memerlukan dua atau lebih sumber
daya dan fasilitass IGD. Contohnya sebagai berikut :
sepsis yang memerlukan pemeriksaan laboratorium,
radiologis dan EKG, demam tifoid dengan komplikasi dan
lain-lain.
(4) Prioritas 4 / ESI 4 (Label Hijau)
Prioritas 4 adalah untuk pasien yang tidak memerlukan
sumber daya. Pasien ini hanya perlu pemeriksaan fisik dan
anamnesis saja. Pengobatan pada pasien dengan prioritas 4
umumnya per oral atau rawat luka sederhana.
(5) Prioritas 5 / ESI 5 (Label Putih )
Prioritas 5 adalah untuk pasien yang tidak memerlukan
sumber daya. Pasien ini hanya perlu pemeriksaan fisik dan
anamnesis saja. Pengobatan pada pasien dengan prioritas 5
umumnya per oral atau rawat luka sederhana.
b) CTAS (Canadian Triage and Acuity Scale)
CTAS adalah sistem triase lima tingkat (level I =
resusitasi, level II = emergent, level III = urgen, level IV =

20
kurang urgen, dan level V = tidak mendesak) yang
didasarkan pada daftar keluhan pasien. Tujuan operasional
utamanya adalah menentukan waktu untuk pemeriksaan
awal pasien oleh dokter (Mirhaghi, 2015; Bullard et al.,
2017).
c) MTS (Manchester Triage Scale)
MTS adalah lima tingkat algoritma triase gawat darurat
yang terus dikembangkan di Inggris dan diadopsi oleh
beberapa negara. MTS telah didukung oleh Asosiasi
Perawat Kecelakaan dan Gawat Darurat (Grouse et al.,
2009; Gräff et al., 2014). Sistem triase MTS dibagi
menjadi 5 klasifikasi warna yaitu Merah (Langsung),
Oranye (sangat mendesak), Kuning (mendesak), Hijau
(standar) dan Biru. (tidak mendesak).
d) ATS (Australasia Triag Scale)
Australasian triage scale (ATS) merupakan triase yang
dikembangkan di Australia dan Selandia baru, terdiri dari
5 kategori dengan waktu penentuan kategori dan
penanganan segera hingga batas waktu maksimal 120
menit sejak kedatangan pasien pada unit gawat darurat.
Kategori ATS menggunakan warna antara lain: Merah
(Kategori 1) = Segera mengancam nyawa, Oranye
(Kategori 2) = Mengancam nyawa, Hijau (Kategori 3) =
Potensi mengancam nyawa, Biru (Kategori 4) = Segera
dan Putih (Kategori 5) = Tidak segera. (Australasian
College For Emergency Medicine, 2016).

21
2.2 Konsep Kecemasan
2.2.1 Definisi kecemasan
Kecemasan atau dalam Bahasa Inggrisnya “anxiety “ berasal dari
Bahasa Latin “agustus” yang berarti kaku, dan “ango,anci”
yang berarti mencekik, yaitu gangguan perasaan ketakutan,
kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak
mengalami gangguan dalam menilai realistis (Reality Testing
Ability), kepribadian masih tetap utuh dan baik (Spilliting
Personality), dan prilaku dapat terganggu tetapi masih dalam
batas waktu normal. Menurut (Siti Sundari, 2004 : 62 dalam
Nixson Manurung, 2016 ), memahami kecemasan sebagai suatu
keadaan yang menggoncangkan karena adanya ancaman pada
kesehatan.
Kecemasan adalah suatu keadaan yang membuat seseorang tidak
nyaman khawatir, gelisah, takut dan tidak tentram disertai
berbagai keluhan fisik, cemas berkaitan dengan perasaan yang
tidak pasti dan tidak berdaya. (Andara, 2019).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan
adalah gangguan perasaan tidak nyaman khawatir, gelisah, tidak
tentram yang mendalam dan berkelanjutan, yang bisa
menimbulkan perasaan ketakutan yang berlebihan. Ketika
merasa cemasan seorang individu merasa tidak nyaman dan takut
musibah akan terjadi padahal musibah tersebut belum tentu
terjadi.
2.2.2 Gejala – Gejala Kecemasan
Menurut (Hawari, 2011), tanda gejala cemas yang ditunjukkan
seseorang bervariasi, tergantung dari beratnya atau tingkatan
yang sering dirasakan oleh individu tersebut. Keluhan yang

22
sering dirasakan oleh seseorang saat mengalami kecemasan
adalah :
2.2.2.1 Gejala Psikologis : firasat buruk, takut akan pikirannya
sendiri, merasa tegang, pernyataan cemas/ khawatir,
tidak tenang, mudah terkejut, mudah tersinggung dan
gelisah.
2.2.2.2 Gejala somatik : sakit kepala, tangan terasa dingin dan
lembab, berdebar-berdebar, sesak nafas, nyeri pada otot
dan tulang, dam sebagainya.
2.2.2.3 Gangguan pola tidur : mimpi yang meneganggkan.
2.2.2.4 Gangguan konsentrasi dan daya ingat.
Menurut (Siti Sundari, 2004 : 62 dalam Nixson Manurung,
2016), Kecemasan adalah suatu keadaan yang menggoncangkan
karena adanya ancaman kesehatan, individu yang tergolong
normal kadang mengalami kecemasan yang menampak, sehingga
dapat disaksikan gejala- gejala fisik dan mental yaitu :
Gejala yang bersifat fisik diantaranya :
a. Jari tangan dingin
b. Dada sesak
c. Detak jantung makin cepat
d. Tidur tidak nyenyak
e. Berkeringat dingin
f. Nafsu makan berkurang
g. Kepala pusing
h. Mual
i. Muntah
j. Diare
k. Tekanan darah tinggi

23
Gejala yang bersifat mental adalah :
a. Tidak tentram
b. Ketakutan dan cemas merasa akan ditimpa bahaya
c. Ingin lari dari kenyataan
d. Tidak dapat memusatkan perhatian
e. Emosi yang kuat dan tidak stabil (mudah marah, depresi)
2.2.3 Faktor –Faktor Penyebab Kecemasan
Blacburn & Davidson (Dalam Triantoro Safaria & Norfans Eka
Saputra, 2012: 51) menjelaskan factor-faktor yang dapat
menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki
seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah
situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman,
serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk
mengendalian dirinya (seperti keadaan emosi serta fokus
kepermasalahannya).
Kemudian Adler dan Rodman (dalam M. Nur Ghufron & Rini
Risnawita, S, 2012 : 145-146) menyatakan terdapat dua factor
yaitu:
2.2.3.1 Pengetahuan negative pada masa lalu
Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada
masa kanak-kanak yaitu timbulnya rasa tidak
menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang
lagi pada masa mendatang, apabila individu menghadapi
situasi yang sama dan juga menimbulkan
ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal
dalam mengikuti tes.
2.2.3.2 Pikiran yang tidak Rasional
Pikiran yang tidak rasional memiliki empat bentuk yaitu:
a. Kegagalan ketastropik, yaitu adanya asumsi dari
individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada

24
dirinya. Individu mengalami kecemasan serta
perasaan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan
dalam mengatasi permasalahannya.
b. Kesempurnaan, individu mengharapkan kepada
dirinya untuk beprilaku sempurna dan tidak memiliki
cacat. Individu menjadikan ukuran kesempurnaan
sebagai target dan sumber yang dapat memberikan
inspirasi.
c. Generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang
berlebihan, ini terjadi pada orang yang memiliki
sedikit pengalaman.
2.2.4 Jenis – Jenis Kecemasan
Kecemasan merupakan suatu perubahan suasana hati, perubahan
didalam dirinya sendiri yang ditimbulkan dalam tanpa adanya
rangsangan dari luar. Menurut (Mustamir Pedak, 2009 : 30
dalam Nixson Manurung, 2016), membagi kecemasan menjadi
tiga yaitu :
2.2.4.1 Kecemasan Rasional
Kecemasan Rasional merupakan suatu ketakutan akibat
adanya objek yang memang mengancam, misalnya
ketika menunggu hasil ujian. Ketakutan ini dianggap
sebagai unsur pokok normal dan mekanisme pertahanan
dasariah kita.
2.2.4.2 Kecemasan Irrasional
Kecemasan irrasional berarti mereka mengalami emosi
dibawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya tidak
dipandang mengancam.
2.2.4.3 Kecemasan Fundamental
Kecemasan Fundamental merupakan suatu pertanyaan
tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan
kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini

25
disebut sebagai kecemasan eksistensial yang
mempunyai peran fundamental bagi kehidupan
manusia.
2.2.5 Tingkat Kecemasan
Menurut Pasaribu dalam (Rahmita, 2017), menyatakan bahwa
kecemasan terbagi menjadi empat tingkatan yaitu :
2.2.5.1 Cemas Ringan
Cemas ringan terjadi saat ketegangan hidup sehari-hari.
Kemampuan seseorang untuk melihat, mendengar, dan
menangkap lebih dari sebelumnya. Selama tahap ini
seseorang waspada dan lapangan presepsi meningkat,
jenis cemas ini dapat menghasilkan pertumbuhan dan
kreatifitas serta dapat memotivasi belajar. Skor untuk
cemas ringan ini adalah 14-20.
2.2.5.2 Cemas Sedang
Cemas Sedang adalah cemas yang dimana seseorang
hanya berfokus pada hal yang penting saja yang
mengakibatkan lapang presepsi menyempit sehingga
individu kurang melihat, mendengar, dan menangkap.
Seseorang memblokir area tertentu tetapi masih bisa
mengikuti perintah jika di berikan arahan untuk
melakukannya. Skor untuk cemas ini adalah 22-27.
2.2.5.3 Cemas Berat
Cemas berat ditandai dengan signifikan di lapang
presepsi. Cemas berat ini cenderung memfokuskan
pada hal yang detail dan tidak berfikir tentang hal lain,
semua prilaku ditunjukan untuk mengurangi cemas dan
dibutuhkan arahan untuk fokus pada area lain. Skor
untuk cemas ini adalah 28-41.

26
2.2.5.4 Panik
Dikaitkan dengan rasa takut dan terror, individu tidak
dapat melakukan hal-hal bahkan dengan arahan saat
mengalami kepanikan. Gejala yang dapat ditimbulkan
apabila seseorang mengalami kepanikan adalah
penurunan kemampuan untuk berhubungan dengan
orang lain, peningkatan aktivitas motoric, presepsi yang
menyempit dan kehilangan pemikiran rasional. Kondisi
panic yang berkepanjangan akan menyebabkan
kelelahan dan kematian, orang panic tidak mampu
berkomunikasi atau berfungsi secara efektif. Kepanikan
dapat diobati dengan aman dan efektif. Skor untuk
kecemasan ini adalah 42-56.
Menurut (Nursalam, 2017), “Hamilton Anxiety Rating
Scale (HRS-A) pertama kali dikembangkan oleh
Hamilton pada tahun 1956. Untuk mengukur semua
tanda kecemasan baik psikis maupun somatic. HRS-A
terdiri dari 14 item pertanyaan untuk mengukur tanda
adanya kecemasan pada anak dan otang dewasa.”
Skala HRS-A penilaian kecemasan terdiri dari 14 item,
yaitu:
a. Perasaan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran
sendiri, mudah tersinggung.
b. Ketegangan merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah
terganggu dan lesu.
c. Ketakutan : takut terhadap gelap, terhadap orang
asing, bila tinggal sendiri dan takut pada binatang
besar.

27
d. Gangguan tidur sukar memulai tidur, terbangun pada
malam hari, tidur tidak puas dan mimpi buruk.
e. Gangguan kecerdasan : Penurunan daya ingat,
mudah lupa dan sulit berkonsentrasi.
f. Perasaan depresi : Hilangnya minat, berkurangnya
kesenangan pada hobi, sedih perasaan tidak
menyenangkan sepanjang hari.
g. Gejala Somatik : Nyeri pada oto-otot dan kaku,
gertakan gigi, suara tidak stabil dan kedutan otot.\
h. Gejala Sensorik : perasaan ditusuk-tusuk,
penglihatan kabur, muka merah dan pucat serta
merasa lemah.
i. Gejala Kardiovaskuler : Takikardi, nyeri di dada,
denyut nadi mengeras, dan detak jantung hilang
sekejap.
j. Gejala Pernapasan : rasa tertekan didada, pernafasan
tercekik, serik menarik nafas panjang dan merasa
nafas pendek.
k. Gejala gastrointestinal : Sulit menelan, obstipasi,
berat badan menurun, mual dan muntah, nyeri
lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan
panas diperut.
l. Gejala Urogenital : sering kencing, tidak dapat
menahan kencing, aminorea, ereksi lemah atau
impotensi.
m. Gejala Vegetatif : Mulut kering, mudah berkeringat,
muka merah, bulu roma berdiri, pusing atau sakit
kepala.
n. Prilaku sewaktu wawancara : Gelisah, jar-jari
gemetar, mengkerut dahi atau kening, muka tegang,
tonus otot meningkat dan nafas pendek dan cepat.

28
Cara penilaian kecemasan adalah dengan
memberikan penilaian dengan kategori :
0 = Tidak ada gejala sama sekali
1 = Ringan / satu gejala yang ada
2 = Sedang / separuh gejala yang ada
3 = Berat / lebih dari separuh gejala yang ada
4 = Sangat berat semua gejala ada
Penentuan derajat kecemasan dengan cara
menjumlahkan skor 1-14 dengan hasil :
Skor kurang dari 14 = Tidak ada kecemasan
Skor 14-20 = Kecemasan ringan
Skor 21-27 = Kecemasan sedang
Skor 28-41 = Kecemasan berat
Skor 42- 52 = Kecemasan berat sekali / panik.
2.3 Hubungan Triase dengan Kecemasan
kecemasan merupakan kondisi psikologis yang pernah dialami oleh
semua orang. Terlebih lagi bagi keluarga pasien yang pertama kali
mengantarkan keluarganya ke IGD dengan berbagai keluhan dari yang
ringan, sedang, dan berat. Setelah di IGD pasien dipilah atau diseleksi
menurut tingkat kegawatannya menggunakan sistem triase. Di
Indonesia sistem triase disebagian rumah sakit sudah banyak yang
menggunakan sistem triase ESI yaitu pembagian label warna hampir
sama dengan sistem triase START, bedanya sistem triase ESI tingkat
keparahan pasien dimulai dengan warna biru untuk pasien resusitasi,
merah untuk emergent, kuning untuk urgent dan hijau untuk non
urgent. Keluarga pasien yang mengantarkan keluarganya pasti ingin
mendapatkan perawatan atau pengobatan dengan cepat agar sakit yang
diderita keluarganya tidak menjadi parah.

29
Pada saat di IGD, pasien yang tidak masuk kedalam kategori triase
warna biru atau merah perawatan atau pengobatan pasien dapat
ditunda sebentar dan perawat atau dokter mendahulukan pasien yang
masuk kategori triase warna biru atau merah karena lebih mengancam
nyawa bila tidak ditangani segera. Situasi seperti ini lah yang dapat
membuat keluarga pasien merasakan kecemasan. Kecemasan akan
berpengaruh pada dukungan dan keputusan keluarga dalam proses
perawatan pasien.
kecemasan keluarga yang ditunjukkan atau dikemukakan oleh
seseorang bervariasi dengan tanda dan gejala sebagai berikut :
perilaku keluarga yang sering bertanya tentang kondisi anggota
keluarganya, bertanya dengan pertanyaan diulang- ulang, berkunjung
diluar jam kunjung dan keluarga takut kehilangan. Menurut donsu
(2017) secara fisik kecemasan ditandai dengan tekanan darah naik,
gelisah, tremor, berkeringat, sakit kepala, pingsan bahkan ada
keluarga pasien yang berteriak, dan marah.
Secara kognitif dapat dilihat saat mempresepsikan sesuatu cenderung
menyempit, penderita tidak bisa menerima rangsangan dari luar,
penderita hanya fokus pada apa yang diperhatikannya, perilaku ini
dapat dilihat dari gerakan tubuhnya seperti : cara bicara berlebihan
dan cepat, tersentak- sentak, secara emosi tidak stabil, takut, dan
gugup. Perilaku kecemasan keluarga seperti ini dapat menghambat
proses perawatan pasien karena keluarga tidak dapat mengambil
keputusan pengobatan pasien dengan pikiran yang tenang.
2.4 Kerangka Konsep
Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014 ) adalah suatu hubungan
yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel variabel
penelitian yaitu :

30
Variabel Independen Variabel Dependen
Skema 2. 1 Kerangka konsep
2.5 Hipotesis
Hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah “ Ada Hubungan
Triase Pasien Dengan Tingkat Kecemasan Keluarga Di IGD RSUD. Dr.
H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin”.
Variabel Independent ( bebas )
Variabel dependent ( terikat )
Tingkat Kecemasan keluarga Triase Pasien