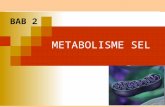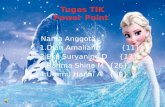BAB -2
description
Transcript of BAB -2
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 JALAN LIGKUNGAN
2.1.1 PENGERTIAN JALAN LINGKUNGAN
Jalan Lingkungan Perumahan adalah jalan yang ada di dalam satuan permukiman/lingkungan
perumahan,terdiri atas :
A.Jalan Lingkungan Perumahan I
B.Jalan Lingkungan Perumahan II (setapak kolektor)
C.Jalan lingkungan Perumahan III (jalan setapak) (Dep.PU, 1985)
Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri
perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah ( UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004, PASAL 8).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jalan lingkungan adalah
Jalan yang ada di lingkungan perumahan yang berfungsi untuk jalur kendaraan dengan kecepatan
rendah.
2.1.2 KRITERIA FISIK JALAN LINGKUNGAN
2.1.2.1. Kualitas Fisik
Menurut Jacobs ( 1995) beberapa kualitas fisik yang wajib terpenuhi pada suatu jalan adalah keter
capaian suasanan yang umum, kondisi yang menghidupkan suasana, keamanan, kenyamanan, keikut
sertaan, dan pertangggung jawaban. Untuk memenuhi kualitas ini, diperlukan dukungan dari unsure-
unsur fisik, seperti jalan tempat manusia berjalan, daerah hijau, perabot jalan (street furniture), dan
utilitas.
1.Keamanan yang tercakup didalamnya :
a.Suatu jalur khusus untuk pejalan kaki yang terpisah dari jalur kendaraan.
b.Trotoar, sebagai pembatas yang paling umum, daerah hijau
(pepohonan, semua dimaksudkan untuk menciptakan zona aman bagi pejalan kaki dan
memberikan kenyamanan serta keindahan.
c.Lampu penerangan yang menerangi jalur pada malam hari dapat
mengurangi perasaan takut serta menerangi objek khusus supaya tampil lebih menarik.
2.Pencapaian yang mudah
a.Arus pejalan kaki biasanya berawal dari bermacam moda transportasi,
maka setidaknyadisediakan tempat penerimaan atau penyelesaian khusus untuk memudahkan
pencapaian jalur.
b.Sepanjang jalur disesuaikan dengan mempersingkat jarak tempuh.
3.Kenyamanan, seperti :
a. Lingkungan berskala manusia, diperlukan perbandingan antara tinggi dan jarak horizontal
setidaknya 1: 4 dengan pengamat melihat kekiri dan ke kanan sebesar 30 derajat.
b. Pemilihan yang sesuai dengan fungsi penggunaan jalur pedestrian berhubunan dengan jenis
alas kaki. Penggunaan material mulus,bertkstur dan tahan terhadap cuaca untuk jalur dengan
kecepatan berjalan cepat - menengah, sedangkan untuk kecepatan berjalan menengah – santai
sebaiknya materil dan penataan yang alamiah dengan jarak antara batu dibuat renggang tanpa diisi
adukan semen , sehingga tetap nyaman untuk dilalui , dan baik untuk peresapan air hujan.
c. Penggunaan jenis material yang berbeda, selain untuk estetika jugabermanfaat bagi penyangdang
cacat tuna netra, dalam penuntun arah jalan melalui teksturnya. Sedangkan penyelesaian dengan
ram sangat memudahkan lajunya kursi roda atau sepeda.
d.Fasilitas peneduh bagi pejalan kaki untuk menghindari terik matahari dan hujan , disepanjang
jalur.
e.Bangku untuk membuat orang betah di jalan, karena mereka dapat
beristirahat, berbincang-bincang, menunggu teman atau hanya membuang waktu sambil duduk.
f. Fasilitas kotak telepon, kotak surat dan tempat sampah adalah elemen perabot jalan yang dapat
berdiri sendiri ataupun disatukan dengan yang lain dan sebaiknya disediakan di beberapa tempat
di sepanjang jalur pedestrian.
g. System utilitas sebaiknya diperhatukan penempatanya sehingga tidak mengganggu pengguna
jalan dan pandangan.
4.Kondisi yang menghidupkan suasana
a. Pedagang informal seperti pedagang kaki lima agar tidak mengganggu jalur, disediakan tempat
yang letaknya cukup strategis dan tetap dapat berhubungan langsung dengan pejalan kaki.
2.1.2.2. PERSYARATAN TEKNIS JALAN LINGKUNGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN, PASAL 16
1)Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 kilometer per
jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter.
2)Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan
bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih.
3)Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.
Baik jalan dalam lingkungan perdesaan di daerah terpencil hingga jalan tol (jalan bebas hambatan)
di ibukota Negara
2.1.2.3. Perkerasan Jalan
Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk
melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah :
- Batu pecah
- Batu belah
- Batu kali
- Hasil samping peleburan baja.
Bahan ikat yang dipakai :
- Aspal
- Semen
- Tanah liat
Berdasarkan bahan ikat, lapisan perkerasan jalan dibagi atas dua kategori :
A. Lapisan perkerasan lentur ( flexibel pavement ) adalah lapisan yang menggunakan aspal
sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisanya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu
lintas ke tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut adalah:
Gambar 2.1 Susunan perkerasan jalan
1. Lapisan permukaan ( surface coarse )
Lapisan permukaan adalah bagian perkerasan jalan yang paling atas. Lapisan tersebut berfungsi
sebagai berikut
a. Lapis perkerasan penahan beban roda, yang mempunyai stabilitas tinggi
untuk menahan roda selama pelayanan.
b. Lapisan kedap air. Air hujan yang jatuh diatasnya tidak meresap ke lapisan di bawahnya dan melemahkan lapisan –lapisan tersebut. c. Lapis aus Lapisan ulang yang langsung menderita gesekan akibat roda kendaraan. d. Lapis – lapis yang menyebabkan beban ke lapis di bawahnya sehingga dapat di pikul oleh lapisan lain dengan daya dukung yang lebih jelek.
Lapis permukaan berdasarkan fungsinya :
1. Lapis non struktural, sebagai lapis aus dan kedap air. 2. Lapis struktural, sebagai lapis yang menahan dan menyebarkan beban roda. Bahan – bahannya terdiri dari batu pecah, kerikil, dan stabilisasi tanah dengan semen atau kapur. Penggunaan bahan aspal diperlukan agar lapisan dapat bersifat kedap air dan memberikan bantuan tegangan tarik yang berarti mempertinggi daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintas. 2. Lapisan pondasi atas ( base coarse )
Lapis pondasi atas adalah bagian lapisan perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah ( atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah ). Fungsi lapis pondasi adalah :
1. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. 2. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah. 3. Bantalan terhadap lapisan permukaan.
Bahan untuk lapis pondasi atas cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai bahan pondasi hendaknya dilakukan penyelidikan dan pertimbangan sebaik- baiknya sehubungan dengan persyaratan teknis. Bermacam- macam bahan alam atau bahan setempat ( CBR > 50 %, PI < 4 % ) dapat digunakan sebagai lapisan pondasi atasantara lain , batu merah, kerikil, stabilisasi tanah dengan semen atau kapur.
3. Lapisan pondasi bawah (sub- base coarse )
Lapis pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dengan tanah dasar.
Fungsi lapis pondasi bawah adalah :
1. Menyebarkan bban roda ke tanah dasar.
2. Efisiensi penggunaan material.
3. Lapis peresapan agar air tanah tidak terkumpul di pondasi.
4. Lapisan partikel-partikel halus dari tanh dasar naik ke lapisan pondasi atas.
Bahannya dari bermacam-macam bahan setempat ( CBR . 20 %, PI < 10 % ) yang relatif jauh
lebih baik dengan tanah dasar dapat digunakan sebagai bahan pondasi bawah. Campuran-campuran
tanah setempat dengan kapur atau semen portland dalam beberapa hal sangat dianjurkan agar dapat
bantuan yang efektif terhadap kestabilan konstruksi perkerasan.
4. Lapisan tanah dasar ( subgrade)
Tanah dasar adalah permukaan tanah semula atau permukaan tanah galian atau permukaan
tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perletakkan bagian-bagian
perkerasan lainya.
Gambar 2.2 Tanah dasar berupa galian
Gambar 2.3 Tanah dasar berupa timbunan
Gambar 2.4 Tanah dasar berupa tanah asli
Persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah :
a. Perubahan bentuk tetap ( deformasi permanen ) dari macam tanah tertentu
akibat beban lalu lintas
b. Sifat kembang susut tanah tertentu akibat perubahan kadar air.
c. Daya dukung tanah yang tidak merata, sukar ditentukan secara pasti ragam
tanah yang sangat berbeda sifat dan kelembabanya.
d. Lendutan atau lendutan balik.
Konstruksi Pondasi
1. Konstruksi Macadam
Gambar 2.5 Pondasi macadam
2. Konstruksi Telford
Konstruksi ini terdiri dari
batu pecah berukuran 15/20 sampai 25/30 yang disusun tegak. Batu-batu kecil diatasnya untuk
menutup pori-pori yang ada dan memberikan permukaan yang rata. Telford digunakan sebagai
lapisan pondasi.
Gambar 2.6 Pondasi telford
Macam- macam lapisan perkerasan lentur :
1.Japat
Jalan padat agregat tahan cuaca, semua jenis jalan tanah ( dapat menggunakan kerikil ) yang
dipadatkan.
2.Soil Cem
Campuran antara tanah setempat dengan semen, dengan perbandingan 6 % yang dipadatkan
di tempat dengan tebal padat 15-20 cm.
3. Burtu ( taburan aspal satu lapis ).
Lapisan penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dangan satu lapis agregat bergradasi
seragam dengan tebal maksimum 2 cm. Lapisan ini biasa dipakai sebagai lapisan non-struktural.
4. Burda (taburan aspal dua lapis ) Lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi
dengan agregat yang dikerjakan dua lapis secara berurutan dengan tebal padat maksimum 3,5 cm.
Lapisan ini digunakan sebagi lapisan non-struktural.
5. Latasir ( Lapis tipis aspal pasir )
Lapisan penutup yang terdiri dari lapisan aspal dan pasir bergradasi menerus dicampur,
dihampar dan dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal padat 1-2 cm. Lpaisan ini digunakan
sebagai lapisan non-struktural. 6. Buras (taburan aspal )
Lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal dan taburan pasir dengan ukuran butir maksimum
3/8 “. Lapisan ini digunakan sebagai lapisan non-struktural.
7. Lapen (lapis penetrasi macadam)
Lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan
seragam diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan lapisan diatasnya dan dipadatkan lapis demi
lapis. Diatas lapen ini diberi taburan aspal dengan agregat penutup. Tebal lapisan 1 lapis 4-10 cm.
Lapisan ini digunakan sebagai lapisan permukaan struktural
8. Lasbutag ( lapis asbuton agregat )
Lapisan yang terdiri dari campuran antara agregat asbuton dengan bahan pelunak
yang diaduk, dihampar dan dipadatkan secara dingin.
Tebal padat tiap lapisan 3-5 cm. Lapisan ini dipakai sebagai lapisan permukaan yang bersifat
struktural.
9. Latasbun ( lapisan tipis asbuton murni )
Lapisan yang terdiri dari campuran antara agregat asbuton dengan bahan pelunak dengan
perbandingan tertentu yang dicampur secara dingin. Tebal padat maksimum 1 cm. Lapisan ini
dipakai sebagai lapisan non struktural.
10. Lataston ( lapis tipis aspal beton ” Hot Rolled Sheets “ HRS )
Lapis penutup yang terdiri dari campuran antara agregat bergradasi menerus. Material pengisi
( filler ) dan aspal panas dengan perbandingan tertentu yang dicampurkan dan dipadatkan dalam
keadaan panas. Tebal padat 2,5-3 cm. Lapis ini digunakan sebagai lapis struktural.
11.Laston ( lapis aspal beton )
Lapis yang terdiri dari campuran aspal keras ( AC ) dan agregat yang mempunyai gradasi menerus
dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu. Lapis ini digunakan sebagai lapis
permukaan struktural dan lapis pondasi, ( asphalt concrete base/asphalt trated base ).
12. Concrete blok ( conblok )
Blok-blok beton misalnya berbentuk segienam disusun diatas lapisan pasir yang diratakan
dengan maksud supaya air tidak tergenang diatas blok beton.
B. Lapisan perkerasan kaku ( rigid pavement )
Perkerasan yang menggunakan bahan ikat semen portland, pelat beton dengan atau tanpa
tulangan diletakkan diatas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian
besar dipikul oleh pelat beton.
Gambar 2. 7 Struktur perkerasan kaku
Lapis pondasi atas dan lapis pondasi bawah memberikan sumbangan yang besar terhadap
gaya dukungan perkerasan terutama didapat dari pelat beton. Hal tersebut disebabkan oleh sifat pelat
beton yang cukup kaku sehingga dapat menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan
tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan dibawahnya.
Jenis-jenis perkerasan kaku antara lain :
1. Perkerasan beton semen
Yaitu perkerasan kaku dengan beton semen sebagai lapis aus. Terdapat empat jenis perkerasan beton
semen :
a. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulang.
b. Perkerasan beton semen bersambung dengan tulang.
c. Perkerasan beton semen bersambung menerus dengan tulang.
d. Perkerasan beton semen pra tekan.
2. Perkerasan komposit
Yaitu perkerasan kaku dengan pelat beton semen sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis
permukaan. Perkerasan kaku ini sering digunakan runway pesawat terbang.
2.1.2.4. FUNGSI JALAN LINGKUNGAN.
Jalan adalah sarana infrastruktur vital yang menunjang aktivitas dan mobilitas kegiatan perekonomian
masyarakat umum. Baik jalan dalam lingkungan perdesaan di daerah terpencil hingga jalan tol (jalan bebas
hambatan) di ibukota Negara.
Dalam PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa jalan adalah sarana transportasi darat
yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,
dan jalan kabel.
Dan jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.Yang membentuk
suatu sistem jaringan jalan yang membentuk satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan
dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan
dalam sati hubungan hierarki.
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 34 Pasal 8, tantang jalan
lingkungan, dijelaskan bahwa jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan, dengan cirri perjalanan jarak dekat dan, kecepatan rendah. Jalan kabupaten
yang pengelolaanya dibawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Pemerintah
Kabupaten terdiri atas:
a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi,
b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota
kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar
desa,
c. Jalan sekunder yang yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan
d. Jalan strategis kabupaten.
Jalan kota yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga atau Tata Kota Pemerintah Kota adalah jalan umum pada jaringan sekunder di dalam. Dan
untuk jalan desa, adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan
kabupaten di dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan
dan/atau antar pemukiman dalam desa.
Pasal 34 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan memuat Ruang Manfaat Jalan yang meliputi :
badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Dimana ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan ( dalam
hal ini Pemerintah ) yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku.
Ruang Manfaat Jalan tersebut biasanya digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur
pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian,
gorong-gorong ( box culvert ), perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Sehingga setiap
orang yang merupakan warga Negara Indonesia dilarang memanfaatkan Ruang manfaat jalan yang
dapat mengganggu jalan sebagai sarana fasilitas umum.Ruang milik jalan sesuai dengan Pasal 40 No
34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jalan paling sedikit memiliki:
a. Jalan bebas hambatan 30 meter,
b. Jalan raya 25 meter,
c. Jalan sedang 15 meter, dan
d.Jalan kecil 11 meter.
Ruang Milik Jalan tersebut diberi tanda yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang
diatur dalam Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Apabila terjadi
gangguan dan hambatan terhadap ruang milik jalan, maka penyelenggara jalan ( pemerintah ) wajib
segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan yang diatur dengan suatu hak tertentu
sesuai dengan perundang-undangan.
Di dalam Pasal 44 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, mengenai Ruang Pengawasan Jalan
dijelaskan sebagai ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah penga-
wasan penyelenggara jalan. Ruang Pengawasan Jalan tersebut diperuntukkan bagi pandangan bebas
pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan ditentukan
dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
a. Jalan arteri primer 15 meter,
b. Jalan kolektor primer 10 meter,
c. Jalan lokal primer 7 meter,
d. Jalan lingkungan primer 5 meter,
e. Jalan arteri sekunder 15 meter,
f. Jalan kolektor sekunder 5 meter,
g. Jalan lokal sekunder 3 meter,
h. Jalan lingkungan sekunder 2 meter, dan
i. Jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu
2.2 KONDISI FISIK JALAN LINGKUNGAN
2.2.1 Kondisi Setting Fisik Jalan Lingkungan
2.2.1.1. Bangunan
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukanya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baikuntuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social dan budaya, maupun kegiatan khusus.
2.2.1.2. Pedagang Kaki Lima ( PKL )
Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyabut penjaja dagangan
yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima.
Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “ kaki” gerobak ( yang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang
dijalanan pada umumnya.
Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan colonial Belanda. Peraturan
pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya dibangun hendaknya menyediakan
sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kai atau sekitar satu setengah
meter.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki
lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah
lantai (tangga) d muka pintu atau di tepi jalan.
Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukan bagi bagian depan bangunan rumah took, dimana
di jaman silam telah terjadi kesepakatan anatra perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari
took lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatau jakur dimanan pejalan kaki
dapat melintas.
Namun ruang selebar kira – kira lima kaki itu tidak lagi berfunsi sabagai jalur lalu lintas bagi
pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang – barang pedagang
kecil, maka dari istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.
Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka ruas jalan untuk pejalan kaki
banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjalan. Kalau dahulu sebutannya adalah pedagang
emperan jalan, lama-lama berubah menjadi pedagang kaki lima. Padahal kalu mau merunut sejarah,
mestinya sebutannya adalah pejalan kaki lima.
2.2.1.3 Pedestrian
Pedestrian berasal dari bahasa Yunani Pedos yang berarti kaki ( Oxford Advace Learner’s
Dictionary of Current Engglish, A.s Horny. Dalam seminar TA 8548, FTA Undip 1996). Dalam
bahasa Inggris, sebagai kata benda pedestrian berarti “ orang yang berjalan kaki “ atau sebagai kata
sifat berarti “ untuk pejalan kaki ( kamus Inggris-Indonesia, Markus, 1996).
Carr (1992) menyebutkan bahwa jalur pedestrian adalah bagian-bagian dari kota dimana
orang bergerak dengan kaki, biasanya di sepanjang sisi jalan baik yang direncanakan ataupun ter
bentuk dengan sendirinya yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainya.
“ Bergerak” berasal dari kata gerak yang berarti peralihan dari tempat atau kedudukan ( tidak diam
saja) sedangkan “ Pergerakan” berarti hal atau keadaan bergerak ( Kamus Besar Bahasa Indonesia,
1989 ).
Standar fisik jalur pedestrian
1. Permukaan
Permukaan harus stabil, kuat, tahan cuca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau
gundukan pada permukaan.. Kaluapun terpakasa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1, 25 cm. Apa
bila menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus dengan konstruksi permanen.
2. Kemiringan
Kemiringan maksimum 7 derajat dan pada setiap jarak 900 cm diharuskan terdapat bagian datar
yang minimal 120 cm.
3. Area istirahat
Terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat dengan menyediakan
tempat duduk santai di bagian tepi.
Gambar 2.8 Fasilitas area istirahat
4. Pencahayaan
Pencahayaan berkisar antara 50 150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan
kebutuhan keamanan.
5. Perawatan
Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.
6. Drainase
Drainase dibuat tegak lurus dengan arah kedalaman maksimal 150 cm, mudah dibersihkan dan
perletakkan lubang dijauhkan dari tepi ram.
7. Ukuran
Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur
pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase dan benda-benda lainnya
yang menghalangi.
1. Tepi pengaman / kanstin
Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra kea rah area yang berbahaya.
Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jlur pedestrian.
Ukuran dan Detail Penerapan Standart.
Gambar 2.9
Gambar 2.10 Penempatan pohon, rambu dan street furniture
Gambar 2.11 Prinsip perencanaan jalur pemandu
Gambar 2.12 Susunan ubin pemandu pada belokan
Dalam sistem jaringan jalur kendaraan (vehicular system0, trotoar (sidewalks)
difungsikan sebagai jalur khusus untuk pejalan kaki.Jalur Khusus yang terpisah dari badan jalan
akan memberikan keamanan pejalan kaki dalam melakukan aktifitas dan melindunginya dari
gangguan kendaraan. Menurut (Untermann, 1984) jalur pedestrian dapat berfungsi sebagai area
rekreasi apaila dibuat dalam bentuk mall atau plaza, sehingga pejalan kaki bebas beraktifitas, aman
dan lebih nyaman. Menurut (Shurvani, 1985) jalur pedestrian merupakan fasilitas ruang terbuka
public. Apabila jalur pedestrian beradad di antara dua titik pusat kegiatan, akan berfungsi sebagai
ruang penghubung yang mendukung kegiatan kawasan.
Sirkulasi jalur pedestrian merupakan bentuk hubungan aktifiras kolektif kawasan, yang bertujuan
untuk kesejahteraan, keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan keindahan. Pengembangan jalur
pedestrian prioritas diarahkan terhadap kualitas visual, dengan demikian jalur pedestrian sebagai
fasilitas public perlu memperhatiakn keindahan linhkungan ( Rubenstein. 1980).
Jalur pedestrian termasuk dalam tipe street karena jalur pedestrian adalah bagian dari kota
dimanan orang bergerak dengan kaki, biasanya disepanjang sisi jalan ( jalur pedestrian ) baik yang
direncanakan ataupun terbentuk dengan sendirinya yang menghubungkan satu tempat dengan tempat
lainnya ataupun tempat orang berjalan kaki yang bebas dan memiliki batas terhadap jalur kendaraan
( Carr, 1992). Sedangkan bentuk fisik dan dimensi jalur pedestrian berbeda berdasarkan
jenis jalan yang dilengkapi dan fungsinya seperti jalan untuk ditinggali (for living), untuk belanja
(for shopping), untuk berjalan (for walking), untuk bersantai (for leisure), atau untuk beraktifitas dan
kombinasi aktifitas lainnya.
2.2.1.4. Street furniture
Perabot jalan adalah objek yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu, termasuk kursi,
trotoar, kotak pos, kotak telepon, lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, tanda jalan, halte
bis, grift bin, halte trem, wc umum, air mancur, dan memorial.
2.2.2 Kondisi Setting Aktifitas di Jalan Lingkungan
2.2.2.1 Aktifitas formal
1. Jalur Kendaraan Bermotor
Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat
asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud
sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Dari sini timbul jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan
perangkutan (transportasi) dari satu tempat ke tempat lain. Di sini terlihat, bahwa transportasi dan
tata guna lahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan transportasi yang
diwujudkan dalam bentuk lalu lintas kendaraan, pada dasarnya merupakan kegiatan yang meng
hubungkan dua lokasi dari tata guna lahan yang mungkin sama atau berbeda.
Perkembangan teknologi di bidang transportasi menuntut adanya perkembangan teknologi
prasarana transportasi berupa jaringan jalan. Sistem transportasi yang berkembang semakin cepat
menuntut perubahan tata jaringan jalan yang dapat menampung kebutuhan lalu lintas yang
berkembang tersebut.
Menurut (Moestikahadi, 2000),Jenis-jenis angkutan yaitu :
a. Angkutan pribadi (individual transit), seperti mobil pribadi, sepeda
motor, sepeda ,atau berjalan kaki
b. Angkutan masal (mass transit), seperti kereta api,bis, opelet, dan sebagainya.
c. Angkutan sewaan (para transit), seperti mobil sewaan, taksi yang menjalani rute tetap atau
yang disewa untuk sekali jalan, dan sebagainya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2005 Pasal 1 menetapkan bahwa, kendaraan
Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
Dalam Peraturan Daerah Tentang Izin Penggunaan Jalan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No 5
menetapkan bahwa, kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak
bermotor.
Dalam Peraturan Daerah Tentang Izin Penggunaan Jalan Bab 1 Ketentuan Umm Pasal 1 No 6
menetapkan bahwa, Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum.
Dalam Peraturan Daerah Tentang Izin Penggunaan Jalan Bab 1 Ketentuan Umm Pasal 1 No
7 menatapkan bahwa, kelas Jalan adalah pembagian jalan yang didasarkan pada kebutuhan
Transportasi pemilihan Moda secara tepat dengan mempertimbangkan keuntungan Karakteristik
masing – masing Moda, perkembangan Teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat, serta
Konstruksi jalan.
Pengertian kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 35
Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum yaitu
Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
2. Pejalan Kaki
Menurut ( Moh T.R dkk, 1999 ) pejalan kaki berdasarkan sarana perjalanannya dapat dikategorikan
sebagai berikut :
1. Pejalan kaki penuh adalah mereka yang mengunakan moda jalan kaki sebagai moda utama,
jalan kaki digunakan sepenuhnya dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.
2. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum adalah pejalan kaki yang menggunakan
moda jalan kaki sebagai moda antara. Biasanya dilakukan dari tempat asal ke
tempat kendaraan umum, atau dari tempat pemberhentian kendaraan umum ke
tempat tujuan akhir.
3. Pejalan kaki pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi adalah mereka yang meng
gunakan moda jalan kaki sebagai moda antara, dari tempat parker kendaraan pribadi ke
tempat kendaraan umum dan dari tempat parkir kendaraan umum ke tempat tujuan akhir
perjalanan.
4. Pejalan kaki pemakai kendaraan pribadi penuh, adalah mereka yang menggunakan
moda jalan kaki sebagai moda antara dari tempat parkir kendaraan ke tempat tujuan
bepergian yang hanya di tempuh dengan berjalan kaki.
Menurut Fruin, ( 1979 ) berjalan kaki merupakan alat pergerakan internal kota, satu –
satunya alat untuk pergerakkan internal kota, satu – satunya alat untuk memenuhi kebutuhan
interaksi tatap muka yang ada di dalam aktifitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan
kota. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda – moda angkutan yang tidak mungkin
dikerjakan oleh moda angkutan yang lain.
Hartini ( 1979 ) dalam tesisnya menyebutkan pejalan kaki adalah orang yang bergerak atau
berpindah dari satu tempat titik tolak ke tempat tujuannya tanpa menggunakan alat bantu yang
ersifat mekanis. Pada hakeketnya manusia adalah pejlan kaki, meskipun manusia semakin tergantung
pada alat transportasi tetapi tetap melakukan kegiatan berjalan kaki sehari – hari.
3. Kebutuhan pejalan kaki
Jalur pejalan kaki (jalur pedestrian) diupayakan mengkaji kemungkinan yang diperlukan
manusia, yang artinya menyadiakan ruang yang memberikan kepuasan bagi pemakainya. Ada
beberapa pendapat mengenai kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh maslow ( dalam
Rutledge 1985 ) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dikelompokan menjadi :
Kebutuhan psikologis seperti, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan relaksasi, ke
butuhan orientasi, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa cinta kasih sayang.
Kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan rasa nyaman ( kenyamanan fisik) seperti perlindungan dari
panas matahari dan hujan, danketersediaan fasilitas – fasilitas fisik yang mendukung aktifitas estetika
dan kenyamanan visual, kebuthan keamanan, kemudahan aksebilitas, kebutuhan melakukan aktifitas
seperti olah raga.
2.2.2.2 Aktifitas Informal
1.Pedagang Kaki lima Pedagang kaki lima merupakan bagian yang tidak dapat lepas dari aktifitas sector informal. Di daerah perkotaan PKL memegang peranan yang cukup penting. Pertumbuhan PKL mengalami peningkatan yang sangat berarti seiring dengan krisis perekonomian yang melanda Indonesia. Begitupun penampilan PKL yang mewarnai wajah sekitar tempat keramaian, terutama dipersimpangan jalan dan pusat perbelanjaan atau pasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan sector informal PKL ini merupakan konsekuensi logis dari adanya dualisme soial ekonomi yang terjadi. Mereka menggunakan tenaga kerja secara maksimum tanpa memerlukan modal yang besar. Dinamika yang berkembang dalam sector informal menghasilkan surplus, yang kemudian diinvestasikan kembali dalam sector ini. Pertumbuhan dan perkembangan sector informal terjadi berdasarkan kekuatan sendiri. Pola penertiban dan pemindahan lokasi usaha selama ini tampak mewarnai kebijakan pemerintah kota. Menimbulkan kehancuran total karena kalangan informal menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi baru. Besarnya potensi yang terdapat di balik pertumbuhan pesat sector informal PKL belum tersosilaisasikan dengan baik sementara permasalahan sector formal PKL itu sendiri berkembang seiring dengan kompleksitasmigrasi yang kini meningkat. Kompleksitas per
masalahan informal ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mulai
melakukan pendekatan secara sistematik. Salah satu pendekatan sistematik yang dilakukan
adalah melakukan kajian karakteristik factor – factor sosial ekonomi mempengaruhi
pertumbuhan sector imformal PKL.