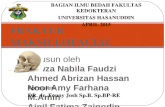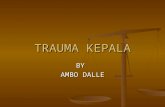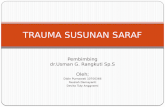77626352-Trauma-Capitis.docx
description
Transcript of 77626352-Trauma-Capitis.docx
BAB I
PENDAHULUAN
Di negara berkembang seperti Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi dan
pembangunan, frekuensinya cenderung makin meningkat. Cedera kepala berperan pada
hampir separuh dari seluruh kematian akibat trauma, mengingat bahwa kepala
merupakan bagian yang tersering dan rentan terlibat dalam suatu kecelakaan. Kasus
cedera kepala terutama melibatkan kelompok usia produktif, yaitu antara 15-44 tahun
dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Penyebab tersering
adalah kecelakaan lalu lintas dan disusul dengan kasus jatuh terutama pada kelompok
usia anak-anak.
Trauma capitis adalah cedera pada kepala yang dapat melibatkan seluruh struktur
lapisan, mulai dari lapisan kulit kepala atau tingkat yang paling “ringan”, tulang
tengkorak, duramater, vaskuler otak, sampai jaringan otaknya sendiri; baik berupa luka
yang tertutup, maupun trauma tembus.
Untuk rujukan penderita cedera kepala, perlu dicantumkan informasi penting
seperti: umur penderita, waktu, mekanisme cedera, status respiratorik dan
kardiovaskuler, pemeriksaan minineurologis (GCS) terutama nilai respon motorik dan
reaksi cahaya pupil, adanya cedera penyerta, dan hasil CT Scan.
Pada penderita harus diperhatikan pernafasan, peredaran darah umum dan
kesadaran, sehingga tindakan resusitasi, anmnesa dan pemeriksaan fisik umum dan
neurologist harus dilakukan secara serentak. Tingkat keparahan cedera kepala harus
segera ditentukan pada saat pasien tiba di Rumah Sakit.
1
A.Kulit Kepala (Scalp)
Kulit kepala terdiri dari 5 lapisanyang disebut SCALP yaitu:
1. Skin atau kulit
2. Connective Tissue atau jaringan penyambung
3. Aponeurosis atau galea aponeurotika yaitu jaringan ikat yang berhubungan
langsung dengan tengkorak
4. Loose areolar tissue atau jaringan penunjang longgar
5. Perikarnium
Kulit kepala memiliki banyak pembuluh darah sehingga bila terjadi perdarahan akibat
laserasi kulit kepala akan menyebabkan banyak kehilangan darah terutama pada anak-
anak atau penderita dewasa yang cukup lama terperangkap sehingga membutuhkan
waktu lama untuk mengeluarkannya.
B.Tulang Tengkorak
Tulang tengkorak atau kranium terdiri dari kalvarium dan basis kranii, di regio temporal
tulang tipis, namun disini dilapisi oleh otot temporalis. Basis kranii berbentuk tidak rata
dan tidak teratur sehingga cedera pada kepala dapat menyebabkan kerusakan pada
bagian dasar otak yang bergerak akibat cedera akselerasi dan deselerasi. Rongga
tengkorak dasar dibagi atas tiga fosa yaitu anterior, media dan posterior. Fosa anterior
adalah tempat lobus frontalis, fosa media tempat lobus temporalis dan fosa posterior
adalah ruang bagi batang otak bawah dan serebelum.
3
C.Meningen
Selaput meningen menutupi seluruh permukaan otak, terdiri dari tiga lapisan yaitu:
duramater, araknoid dan piamater. Duramater adalah selaput yang keras, terdiri atas
jaringan ikat fibrosa yang melekat erat dengan tabula interna atau bagian dalam
kranium. Duramater tidak melekat dengan lapisan dibawahnya (araknoid), terdapat
ruang subdural.
Pada cedera kepala, pembuluh vena yang berjalan pada permukaan otak menuju sinus
sagitalis superior di garis tengah atau disebut Bridging veins, dapat mengalami robekan
dan menyebabkan perdarahan subdural. Arteri-arteri meningea terletak antara duramater
dan tabula interna tengkorak, jadi terletak di ruang epidural. Yang paling sering
mengalami cedera adalah arteri meningea media yang terletak pada fosa temporalis (fosa
media). Dibawah duramater terdapat araknoid yang merupakan lapisan kedua dan
tembus pandang. Lapisan yang ketiga adalah piamater yang melekat erat pada
permukaan korteks serebri. Cairan serebrospinal bersirkulasi diantara selaput araknoid
dan piameter dalam ruang sub araknoid.
D.Otak
Otak manusia terdiri dari serebrum,serebelum dan batang otak. Serebrum terdiri atas
hemisfer kanan dan kiri yang dipisahkan oleh falks serebri(lipatan duramater yang
berada di inferior sinus sagitalis superior). Hemisfer otak yang mengandung pusat bicara
sering disebut sebagai hemisfer dominan. Lobus frontalis berkaitan dengan fungsi
emosi, fungsi motorik dan pada sisi dominan mengandung pusat ekspresi bicara (area
bicara motorik). Lobus parietalis berhubungan dengan orientasi ruang dan fungsi
sensorik. Lobus temporalis mengatur fungsi memori tertentu. Lobus occipitalis
berukuran lebih kecil dan berfungsi dalam penglihatan. Batang otak terdiri dari
mesensefalon, pons dan medula oblongata. Mesensefalon dan pons bagian atas berisi
sistem aktivasi retikulasi yang berfungsi dalam kesadaran dan kewaspadaan. Pada
medula oblongata berada pusat vital kardiorespiratorik yang terus memanjang sampai
medula spinalis di bawahnya. Serebellum bertanggung jawab dalam fungsi koordinasi
dan keseimbangan terletak dalam fosa posterior, berhubungan dengan medula spinalis
batang otak dan kedua hemisfer serebri.
4
E.Cairan Serebrospinal
Cairan serebrospinal dihasilkan oleh pleksus khoroideus dengan kecepatan
produksi sebanyak 30 ml/jam. Pleksus khorideus terletak di ventrikel lateralis baik
kanan maupun kiri, mengalir melalui foramen monro ke dalam ventrikel tiga.
Selanjutnya melalui akuaduktus dari sylvius menuju ventrikel ke empat, selanjutnya
keluar dari sistem ventrikel dan masuk ke ruang subaraknoid yang berada diseluruh
permukaan otak dan medula spinalis. CSS akan diserap ke dalam sirkulasi vena melalui
granulasio araknoid yang terdapat pada sinus sagitalis superior. Adanya darah dalam
CSS dapat menyumbat granulasio araknoid sehingga mengganggu penyerapan CSS dan
menyebabkan kenaikan tekanan intra kranial (hidrosefalus komunikans)
F.Tentorium
Tentorium serebelli membagi ruang tengkorak menjadi supratentorial dan
infratentorial. Mesensefalon menghubungkan hemisfer serebri dengan batang otak
berjalan melalui celah lebar tentorium serebeli yang disebut insisura tentorial. Nervus
oculomotorius(N.III) berjalan di sepanjang tentorium, dan saraf ini dapat tertekan pada
6
keadan herniasi otak yang umumnya dikibatkan oleh adanya massa supratentorial atau
edema otak. Bagian otak yang sering terjadi herniasi melalui insisura tentorial adalah
sisi medial lobus temporalis yang disebut girus unkus. Herniasi Unkus menyebabkan
juga penekanan traktus piramidalis yang berjalan pada otak tengah. Dilatasi pupil
ipsilateral disertai hemiplegia kontralateral dikenal sebagai sindrom klasik herniasi
tentorial. Jadi, umumnya perdarahan intrakranial tedapat pada sisi yang sama dengan sisi
pupil yang berdilatasi, walaupun tidak selalu.
I.2.Fisiologi
A. Tekanan Intrakranial
Berbagai proses patologis yang mengenai otak dapat mengakibatkan kenaikan tekanan
intrakranial yang selanjutnya akan mengganggu fungsi otak yang akhirnya berdampak
buruk terhadap kesudahan penderita. Dan tekanan intrakranial yang tinggi dapat
menimbulkan konsekuensi yang mengganggu fungsi otak dan tentunya mempengaruhi
pula kesembuhan penderita. Jadi, kenaikan tekanan intrakranial (TIK) tidak hanya
merupakan indikasi adanya masalah serius dalam otak tetapi justru sering merupakan
masalah utamanya. TIK normal pada saat istirahat kira-kira 10 mmHg (136 mmH2O),
TIK lebih tinggi dari 20 mmHg dianggap tidak normal dan TIK lebih dari 40 mmHg
termasuk dalam kenaikan TIK berat. Semakin tinggi TIK setelah cedera kepala, semakin
buruk prognosisnya.
B. Doktrin Monro-Kellie
Adalah suatu konsep sederhana yang dapat menerangkan pengertian dinamika TIK.
Konsep utamanya adalah bahwa volume intrakranial selalu konstan, karena rongga
kranium pada dasarnya merupakan rongga yang tidak mungkin mekar. TIK yang normal
tidak berarti tidak adanya lesi masa intrakranial, karena TIK umumnya tetap dalam batas
normal sampai kondisi penderita mencapai titik dekompensasi dan memasuki fase
ekspansional kurva tekanan-volume. Nilai TIK sendiri tidak dapat menunjukkan
kedudukan pada garis datar kurva berapa banyak volume lesi masanya.
7
C. Tekanan Perfusi Otak (TPO)
Mempertahankan tekanan daerah yang adekuat pada penderita cedera kepala adalah
sangat penting, dan ternyata dalam observasi selanjutnya TPO adalah indikator yang
sama pentingnya dengan TIK. TPO mempunyai formula sebagai berikut:
TPO = TAR – TIK
(TAR = Tekanan Arteri Rata-rata; Mean arterial pressure)
TPO kurang dari 70 mmHg umumnya berkaitan dengan kesudahan yang buruk pada
penderita cedera kepala. Pada keadaan TIK yang tinggi ternyata sangat penting untuk
tetap mempertahankan tekanan darah yang normal. Beberapa penderita tertentu bahkan
membutuhkan tekanan darah yang diatas normal untuk mempertahankan TPO yang
adekuat. Mempertahankan TPO adalah prioritas yang sangat penting dalam
penatalaksanaan penderita cedera kepala berat.
D. Aliran Darah ke Otak (ADO)
ADO normal ke dalam otak kira-kira 50 ml/100 gr jaringan otak per menit. Bila ADO
menurun sampai 20-25 ml/100 gr/menit maka aktivitas EEG akan hilang dan pada ADO
5 ml/100 gr/menit sel-sel otak mengalami kematian dan terjadi kerusakan menetap. Pada
penderita non-trauma, fenomena autoregulasi mempertahankan ADO pada tingkat yang
konstan apabila tekanan arteri rata-rata 50-160 mmHg. Bila tekanan arteri rata-rata
dibawah 50 mmHg, ADO menurun curam dan bila tekanan arteri rata-rata di atas 160
mmHg terjadi dilatasi pasif pembuluh darah otak dan ADO meningkat. Mekanisme
autoregulasi sering mengalami gangguan pada penderita cedera kepala. Akibatnya,
penderita-penderita tersebut sangat rentan terhadap cedera otak sekunder karena iskemia
sebagai akibat hipotensi yang tiba-tiba. Sekali mekanisme kompensasi tidak bekerja dan
8
terjadi kenaikan eksponensial TIK, perfusi otak sangat berkurang, terutama pada
penderita yang mengalami hipotensi. Karenanya bila terdapat hematoma intra cranial,
haruslah dikeluarkan sedini mungkin dan tekanan darah yang adekuat tetap harus
dipertahankan.
II.MEKANISME DAN PATOLOGI
Cedera kepala dapat terjadi akibat benturan langsung atau tanpa benturan
langsung pada kepala. Kelainan dapat berupa cedera otak fokal atau difus dengan atau
tanpa fraktur tulang tengkorak.
Berdasarkan patofisiologinya cedera kepala dibagi menjadi cedera kepala primer
dan cedera kepala sekunder . Cedera kepala primer merupakan cedera yang terjadi saat
atau bersamaan dengan kejadian cedera, dan merupakan suatu fenomena mekanik.
Cedera ini umumnya menimbulkan lesi permanen. Tidak banyak yang bisa dilakukan
kecuali membuat fungsi stabil, sehingga sel-sel yang sakit dapat menjalani proses
penyembuhan yang optimal. Cedera kepala primer mencakup fraktur tulang, cedera
fokal dan cedera otak difusa. Farktur tulang kepala dapat terjadi dengan atau tanpa
kerusakan otak. Cedera fokal, kelainan ini mencakup kontusi kortikal, hematom
subdural, epidural, dan intraserebral yang secara makroskopis tampak dengan mata
telanjang sebagai suatu kerusakan yang berbatas tegas. Cedera otak difusa berkaitan
dengan disfungsi otak yang luas, serta biasanya tidak tampak secara makroskopis.
Cedera kepala skunder merupakan proses lanjutan dari cedera primer dan lebih
merupakan fenomena metabolik. Pada penderita cedera kepala berat, pencegahan cedera
kepala skunder dapat mempengaruhi tingkat kesembuhan/keluaran penderita .
Penyebab cedera kepala skunder antara lain; penyebab sistemik (hipotensi,
hipoksemia, hipo/hiperkapnea, hipertermia, dan hiponatremia) dan penyebab intracranial
(tekanan intrakranial meningkat, hematoma, edema, pergeseran otak (brain shift),
vasospasme, kejang, dan infeksi) (1,
Aspek patologis dari cedera kepala antara lain; hematoma epidural (perdarahan
yang terjadi antara tulang tengkorak dan dura mater), perdarahan subdural (perdarahan
yang terjadi antara dura mater dan arakhnoidea), higroma subdural (penimbunan cairan
antara dura mater dan arakhnoidea), perdarahan subarakhnoidal cederatik (perdarahan
9
yang terjadi di dalam ruangan antara arakhnoidea dan permukaan otak), hematoma
serebri (massa darah yang mendesak jaringan di sekitarnya akibat robekan sebuah
arteri), edema otak (tertimbunnya cairan secara berlebihan didalam jaringan otak),
kongesti otak (pembengkakan otak yang tampak terutama berupa sulsi dan ventrikel
yang menyempit), cedera otak fokal (kontusio, laserasio, hemoragia dan hematoma
serebri setempat), lesi nervi kranialis dan lesi sekunder pada cedera otak
Cedera kepala dapat terjadi akibat benturan langsung atau tanpa benturan
langsung pada kepala. Kelainan dapat berupa cedera otak fokal atau difus dengan atau
tanpa fraktur tulang tengkorak.Dalam mekanisme cedera kepala dapat terjadi peristiwa
contre coup dan coup. Contre coup dan coup pada cedera kepala dapat terjadi kapan saja
pada orang-orang yang mengalami percepatan pergerakan kepala. Cedera kepala pada
coup disebabkan hantaman pada otak bagian dalam pada sisi yang terkena sedangkan
contre coup terjadi pada sisi yang berlawanan dengan daerah benturan .
III.KLASIFIKASI CEDERA KEPALA
Cedera kepala diklasifikasikan dalam berbagai aspek. Secara praktis dikenal 3 deskripsi
klasifikasi yaitu berdasarkan mekanisme, berat dan morfologi
III.1.Berdasarkan mekanismenya cedera kepala dibagi atas;
1. Cedera kepala tumpul; biasanya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, jatuh atau
pukulan benda tumpul . Pada cedera tumpul terjadi akselerasi dan deselerasi yang
cepat menyebabkan otak bergerak di dalam rongga cranial dan melakukan kontak
pada protuberans tulang tengkorak
10
2. Cedera tembus; disebabkan oleh luka tembak ataupun tusukan
III.2.Berdasarkan morfologinya cedera kepala dikelompokkan menjadi;
1. Fraktur kranium; Fraktur tengkorak dapat terjadi pada atap dan dasar tengkorak .
Fraktur dapat berupa garis/ linear, mutlipel dan menyebar dari satu titik (stelata)
dan membentuk fragmen-fragmen tulang (kominutif). Fraktur tengkorak dapat
berupa fraktur tertutup yang secara normal tidak memerlukan perlakuan spesifik
dan fraktur tertutup yang memerlukan perlakuan untuk memperbaiki tulang
tengkorak .
11
2. Lesi intrakranial; dapat berbentuk lesi fokal (perdarahan epidural, perdarahan
subdural, kontusio, dan peradarahan intraserebral), lesi difus dan terjadi secara
bersamaan .
Perdarahan epidural
Hematoma epidural merupakan pengumpulan darah diantara tengkorak dengan
duramater (hematom ekstradural). Cirinya berbentuk bikonveks atau menyerupai lensa
cembung. Sering terletak di area temporal atau temporo-parietal yang disebabkan oleh
robeknya arteri meningea media akibat retaknya tulang tengkorak. Gumpalan darah
yang terjadi dapat berasal dari pembuluh arteri, namun pada sepertiga kasus dapat terjadi
akibat perdarahan vena, karena tidak jarang perdarahan epidural terjadi akibat robeknya
sinus venosus terutama pada region parieto oksipital dan pada fosa posterior. Walaupun
secara relatif perdarahan epidural jarang terjadi (0,5% dari seluruh penderita cedera
kepala dan 9% dari penderita yang dalam keadaan koma), namun harus dipertimbangkan
karena memerlukan tindakan diagnostik maupun operatif yang cepat. Perdarahan
epidural bila ditolong segera pada tahap dini, prognosisnya sangat baik karena kerusakan
langsung akibat penekanan gumpalan darah pada jaringan otak tidak terlalu lama.
Keberhasilan pada penderita perdarahan epidural berkaitan langsung dengan status
neurologis penderita sebelum pembedahan. Penderita dengan perdarahan epidural dapat
menunjukkan interval lucid yang klasik atau keadaan dimana penderita yang semula
mampu bicara lalu tiba-tiba meninggal (talk and die). Keputusan perlunya suatu
tindakan operatif memang tidak mudah dan memerlukan pendapat dari seorang ahli
bedah saraf.
Gambar: Perdarahan epidural
12
Gambar: Epidural Hematoma
Perdarahan subdural
Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan epidural (kira-kira 30%
dari cedera kepala berat). Perdarahan ini sering terjadi akibat robeknya vena-vena
jembatan yang terletak antara korteks serebri dan sinus venosus tempat vena tadi
bermuara, namun dapat juga terjadi akibat laserasi pembuluh arteri pada permukaan
otak. Perdarahan subdural biasanya menutupi seluruh permukaan hemisfer otak dan
kerusakan otak di bawahnya lebih berat dan prognosisnya pun jauh lebih buruk daripada
perdarahan epidural. Angka kematian yang tinggi pada perdarahan ini hanya dapat
diturunkan dengan tindakan pembedahan yang cepat dan penatalaksanaan
medikamentosa yang agresif.
13
Gambar :Perdarahan subdural
Gambar: Subdural Hematom
Kontusio dan perdarahan intraserebral
Kontusio serebri murni biasanya jarang terjadi. Diagnosis kontusio serebri
meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan CT scan dalam pemeriksaan
cedera kepala. Kontusio serebri hampir selalu berkaitan dengan perdarahan subdural
akut. Kontusio serebri sangat sering terjadi di frontal dan lobus temporal, walaupun
dapat terjadi juga pada setiap bagian otak, termasuk batang otak dan serebelum. Batas
perbedaan antara kontusio dan perdarahan intraserebral traumatika memang tidak jelas.
Kontusio serebri dapat saja dalam waktu beberapa jam atau hari mengalami evolusi
membentuk perdarahan intraserebral.
Cedera difus
Cedera otak difus merupakan kelanjutan kerusakan otak akibat cedera akselerasi
dan deselerasi, dan ini merupakan bentuk yang sering terjadi pada cedera kepala.
Komosio serebri ringan adalah cedera dimana kesadaran tetap tidak terganggu namun
terjadi disfungsi neurologis yang bersifat sementara dalam berbagai derajat. Cedera ini
sering terjadi, namun karena ringan kerap kali tidak diperhatikan. Bentuk yang paling
14
ringan dari kontusio ini adalah keadaan bingung dan disorientasi tanpa amnesia.
Sindroma ini pulih kembali tanpa gejala sisa sama sekali. Cedera komosio yang lebih
berat menyebabkan keadaan bingung disertai amnesia retrograd dan amnesia antegrad
(keadaan amnesia pada peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah cedera).
Komosio serebri klasik adalah cedera yang mengakibatkan menurunnya atau
hilangnya kesadaran. Keadaan ini selalu disertai dengan amnesia pasca trauma dan
lamanya amnesia ini merupakan ukuran beratnya cedera. Hilangnya kesadaran biasanya
berlangsung beberapa waktu lamanya dan reversibel. Dalam definisi klasik penderita ini
akan kembali sadar dalam waktu kurang dari 6 jam. Banyak penerita dengan komosio
serebri klasik pulih kembali tanpa cacat neurologis selain amnesia terhadap peristiwa
yang terjadi, namun pada beberapa penderita dapat timbul defisit neurologis untuk
beberapa waktu. Defisit neurologis itu misalnya kesulitan mengingat, pusing, mual,
anosmia, dan depresi serta gejala lainnya. Gejala-gejala ini dikenal sebagai sindroma
pasca komosio yang dapat cukup berat.
Cedera aksonal difus (Diffuse Axonal Injury, DAI) adalah keadaan dimana penderita
mengalami koma pasca cedera yang berlangsung lama dan tidak diakibatkan oleh suatu
lesi masa atau serangan iskemia. Biasanya penderita dalam keadaan koma yang dalam
dan tetap koma selama beberapa waktu. Penderita sering menunjukkan gejala
dekortikasi atau deserebrasi dan bila pulih sering tetap dalam keadaan cacat berat, itupun
bila bertahan hidup. Penderita-penderita sering menunjukkan gejala disfungsi otonom
seperti hipotensi, hiperhidrosis dan hiperpireksia dan dulu diduga akibat cedera otak
karena hipoksia secara klinis tidak mudah, dan memang kedua keadaan tersebut sering
terjadi bersamaan.
III.3.Berdasarkan beratnya cedera kepala dikelompokkan menjadi
Cedera Kepala Ringan (CKR) → termasuk didalamnya Laseratio dan
Commotio Cerebri
o Skor GCS 13-15
o Tidak ada kehilangan kesadaran, atau jika ada tidak lebih dari 10
menit
o Pasien mengeluh pusing, sakit kepala
15
o Ada muntah, ada amnesia retrogad dan tidak ditemukan kelainan
pada pemeriksaan neurologist.
Cedera Kepala Sedang (CKS)
o Skor GCS 9-12
o Ada pingsan lebih dari 10 menit
o Ada sakit kepala, muntah, kejang dan amnesia retrogad
o Pemeriksaan neurologis terdapat lelumpuhan saraf dan anggota
gerak.
Cedera Kepala Berat (CKB)
o Skor GCS <8
o Gejalnya serupa dengan CKS, hanya dalam tingkat yang lebih
berat
o Terjadinya penurunan kesadaran secara progesif
o Adanya fraktur tulang tengkorak dan jaringan otak yang terlepas.
IV.GAMBARAN KLINIS
Gambaran klinis ditentukan berdasarkan derajat cedera dan lokasinya. Derajat cedera
dapat dinilai menurut tingkat kesadarannya melalui system GCS, yakni metode EMV
(Eyes, Verbal, Movement)
1. Kemampuan membuka kelopak mata (E)
Secara spontan 4
Atas perintah 3
Rangsangan nyeri 2
Tidak bereaksi 1
2. Kemampuan komunikasi (V)
Orientasi baik 5
Jawaban kacau 4
Kata-kata tidak berarti 3
Mengerang 2
Tidak bersuara 1
3. Kemampuan motorik (M)
Kemampuan menurut perintah 6
Reaksi setempat 5
16
Menghindar 4
Fleksi abnormal/Decorticate 3
Ekstensi/Decerebrate 2
Tidak bereaksi 1
Pemeriksaan korban cedera kepala yang kesadarannya baik mencakup pemeriksaan
neurologis yang lengkap. Sedangkan pada penderita yang kesadarannya menurun
pemeriksaan yang diutamakan adalah yang dapat memberikan pedoman dalam
penanganan di unit gawat darurat, yaitu:
1. tingkat kesadaran
2. Kekuatan fungsi motorik
3. Ukuran pupil dan responsnya terhadap cahaya
4. Gerakan bola mata (refleks okulo-sefalik dan vestibuler)
Sehubungan dengan tingginya insidensi kelainan/cedera sistemik penyerta (lebih dari
50%) pada kasus-kasus cedera kepala berat, maka di dalam evaluasi klinis perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Cedera daerah kepela dan leher: laserasi, perdarahan, otorre,
rinorre, racoon’s eyes (ekhimosis periorbital), atau Battle’s sign(ekhimosis
retroaurikuler).
2. Cedera daerah toraks: fraktur iga, pneumotoraks,
hematotoraks, temponade jantung (bunyi jantung melemah, distensi vena
jugularis dan hipotensi aspirasi atau ARDS (Acute Respiratory Distress
Syndrome)
3. Cedera daerah abdomen: khususnya laserasihepar, lien atau
ginjal. Adanya perdarahan ditandai dengan gejala akut abdomen yang tegang
dan distensif.
17
4. Cedera derah pelvis: cedera pada penderita nonkomatus.
Biasanya, klinisnya tidak jelas dan membutuhkan konfirmasi radiologis.
Cedera ini sering berkaitan dengan kejadian kehilangan darah yang okult.
5. Cedera daerah spinal: trauma kepala dan spinal khususnya
derah servikal dapat terjadi secara bersamaan.
6. Cedera ekstremitas: dapat melibatkan jaringan tulang atau
jaringan lunak(otot, saraf, pembuluh darah).
VI.PEMERIKSAAN PENUNJANG
Yang dapat dilakukan pada pasien dengan trauma kapitis adalah:
1. CT-Scan
Untuk melihat letak lesi dan adanya kemungkinan komplikasi jangka pendek.
2. Lumbal Pungsi
Untuk menentukan ada tidaknya darah pada LCS harus dilakukan sebelum 6 jam
dari saat terjadinya trauma
3. EEG
Dapat digunakan untuk mencari lesi
4. Roentgen foto kepala
Untuk melihat ada tidaknya fraktur pada tulang tengkorak
VII.PENATALAKSANAAN
Penatalaksanaan awal penderita cedara kepala pada dasarnya memikili tujuan untuk
memantau sedini mungkin dan mencegah cedera kepala sekunder serta memperbaiki
keadaan umum seoptimal mungkin sehingga dapat membantu penyembuhan sel-sel otak
yang sakit . Untuk penatalaksanaan penderita cedera kepala, Adveanced Cedera Life
Support (2004) telah menepatkan standar yang disesuaikan dengan tingkat keparahan
cedera yaitu ringan, sedang dan berat .
Penatalaksanaan penderita cerdera kepala meliputi survei primer dan survei
sekunder. Dalam penatalaksanaan survei primer hal-hal yang diprioritaskan antara lain :
A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability), dan E (exposure/environmental
control) yang kemudian dilanjutkan dengan resusitasi. Pada penderita cedera kepala
khususnya dengan cedera kepala berat survei primer sangatlah penting untuk mencegah
cedera otak sekunder dan menjaga homeostasis otak .
18
Kelancaran jalan napas (airway) merupakan hal pertama yang harus
diperhatikan. Jika penderita dapat berbicara maka jalan napas kemungkinan besar dalam
keadaan adekuat. Obstruksi jalan napas sering terjadi pada penderita yang tidak sadar,
yang dapat disebabkan oleh benda asing, muntahan, jatuhnya pangkal lidah, atau akibat
fraktur tulang wajah. Usaha untuk membebaskan jalan napas harus melindungi vertebra
servikalis (cervical spine control), yaitu tidak boleh melakukan ekstensi, fleksi, atau
rotasi yang berlebihan dari leher. Dalam hal ini, kita dapat melakukan chin lift atau jaw
thrust sambil merasakan hembusan napas yang keluar melalui hidung. Bila ada
sumbatan maka dapat dihilangkan dengan cara membersihkan dengan jari atau suction
jika tersedia. Untuk menjaga patensi jalan napas selanjutnya dilakukan pemasangan pipa
orofaring. Bila hembusan napas tidak adekuat, perlu bantuan napas. Bantuan napas dari
mulut ke mulut akan sangat bermanfaat (breathing). Apabila tersedia, O2 dapat
diberikan dalam jumlah yang memadai. Pada penderita dengan cedera kepala berat atau
jika penguasaan jalan napas belum dapat memberikan oksigenasi yang adekuat, bila
memungkinkan sebaiknya dilakukan intubasi endotrakheal .
Status sirkulasi dapat dinilai secara cepat dengan memeriksa tingkat kesadaran
dan denyut nadi (circulation). Tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mencari ada
tidaknya perdarahan eksternal, menilai warna serta temperatur kulit, dan mengukur
tekanan darah. Denyut nadi perifer yang teratur, penuh, dan lambat biasanya
menunjukkan status sirkulasi yang relatif normovolemik. Pada penderita dengan cedera
kepala, tekanan darah sistolik sebaiknya dipertahankan di atas 100 mmHg untuk
mempertahankan perfusi ke otak yang adekuat. Denyut nadi dapat digunakan secara
kasar untuk memperkirakan tekanan sistolik. Bila denyut arteri radialis dapat teraba
maka tekanan sistolik lebih dari 90 mmHg. Bila denyut arteri femoralis yang dapat
teraba maka tekanan sistolik lebih dari 70 mmHg. Sedangkan bila denyut nadi hanya
teraba pada arteri karotis maka tekanan sistolik hanya berkisar 50 mmHg. Bila ada
perdarahan eksterna, segera hentikan dengan penekanan pada luka .
Setelah survei primer, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu resusitasi. Cairan
resusitasi yang dipakai adalah Ringer Laktat atau NaCl 0,9%, sebaiknya dengan dua
jalur intra vena. Pemberian cairan jangan ragu-ragu, karena cedera sekunder akibat
hipotensi lebih berbahaya terhadap cedera otak dibandingkan keadaan udem otak akibat
pemberian cairan yang berlebihan. Posisi tidur yang baik adalah kepala dalam posisi
datar, cegah head down (kepala lebih rendah dari leher) karena dapat menyebabkan
bendungan vena di kepala dan menaikkan tekanan intracranial .
19
Pada penderita cedera kepala berat cedera otak sekunder sangat menentukan
keluaran penderita. Survei sekunder dapat dilakukan apabila keadaan penderita sudah
stabil yang berupa pemeriksaan keseluruhan fisik penderita. Pemeriksaan neurologis
pada penderita cedera kepala meliputi respon buka mata, respon motorik, respon verbal,
refleks cahaya pupil, gerakan bola mata (doll’s eye phonomenome, refleks okulosefalik),
test kalori dengan suhu dingin (refleks okulo vestibuler) dan refleks kornea .
Tidak semua pederita cedera kepala harus dirawat di rumah sakit. Indikasi
perawatan di rumah sakit antara lain; fasilitas CT scan tidak ada, hasil CT scan
abnormal, semua cedera tembus, riwayat hilangnya kesadaran, kesadaran menurun, sakit
kepala sedang-berat, intoksikasi alkohol/obat-obatan, kebocoran liquor (rhinorea-
otorea), cedera penyerta yang bermakna, GCS<15>.
Terapi medikamentosa pada penderita cedera kepala dilakukan untuk
memberikan suasana yang optimal untuk kesembuhan. Hal-hal yang dilakukan dalam
terapi ini dapat berupa pemberian cairan intravena, hiperventilasi, pemberian manitol,
steroid, furosemid, barbitirat dan antikonvulsan .
Indikasi pembedahan pada penderita cedera kepala bila hematom intrakranial
>30 ml, midline shift >5 mm, fraktur tengkorak terbuka, dan fraktur tengkorak depres
dengan kedalaman >1 cm .
20
ALGORITME 1PENATALAKSANAAN CEDERA KEPALA RINGAN
Definisi : penderita sadar dan berorientasi-(GCS 14-15) Riwayat : Nama, umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan Mekanisme cedera Waktu cedera Tidak sadar segera setelah cedera Tingkat kewaspadaan Amnesia : Retrograde, Antegrade Sakit kepala : ringan, sedang, berat Kejang
Pemeriksaan umum untuk menyingkirkan cedera sistcmik.Pemeriksaan neurologis terbatas.Pemeriksaan ronsen vertebra servikal dan lainnya sesuai indikasi.Pemeriksaan kadar alkohol darah dan zat toksik dalam urine.Pemeriksaan CT scan kepala sangat ideal pads setiap penderita cedera kepala ringan, kecuali bila memang sama sekali asimtomatik dan pemeriks-'-n neurologis normal.
Observasi atau dirawat di RS CT scan tidak ada CT scan abnormal Semua cedera tembus Riwayat hilang kesadaran Kesadaran menurun Sakit kepala sedang-berat Intoksikasi alkohol/obat-obatan Fraktur tengkorak Rhinorea-otorea Cedera penyerta yang bermakna Tak ada keluarga di rumah Tidak mungkin kembali ke RS segera Amnesia
Dipulangkan dari RS Tidak memenuhi kriteria rawat. Diskusikan kemungkinan kembali bila memburuk dan berikan lembar observasi. Jadwalkan untuk kontrol ulang di poliklinik biasanya setelah 1 minggu
21
ALGORITME 2PENATALAKSANAAN CEDERA KEPALA SEDANG
Definisi : Penderita biasanya tampak kebingungan atau mengantuk, namun masih mampu menuruti perintah-perintah sederhana (GCS : 9-13).
Pemeriksaan awal : Sama dengan untuk cedera kepala ringan ditarnbah pemeriksaan darah
sederhana Pemeriksaan CT scan kepala Dirawat untuk observasi
Setelah dirawat Pemeriksaan neurologis periodik, Pemmksaan CT scan ulang bila kondisi penderita memburuk atau bila
penderitaakan dipulangkan.
Bila kondisi membaik (90%) Pulang Kontrol di poliklinik.
Bila kondisi memburuk (10%)
Bila penderita tidak mampu melakukan perintah-perintah lagi, segera lakukan pemeriksaan CT scan ulang dan penatalaksanaan sesuai protokol cedera kepala berat.
PENATALAKSANAAN AWAL CEDERA KEPALA BERAT
Definisi : penderita tidak mampu melakukan perintah-perintah sederhana karena kesadaran yang menurun (GCS 3-8)Pemeriksaan dan penatalaksaan
ABCDE Primary Sunny dan resusitasi Secondary Survey dan riwayat AMPLE Re-evaluasi neurologic
Respon buka mats • Reaksi Cahaya pupil Respon motorik • Refleks okulo sefalik (Doll's eyes) Respon verbal • Refleks Okulovestibuler (Test Kalori)
Obat-obatan Manitol • Antikonvulsan Hiperventilasi sedangTes Diagnostik (sesuai urutan)
CT Scan (semua penderita)
22
Ventrikulografi udara Angiogram
ALGORITME 3DPL - ULTRASONOGRAFI - CT SCAN PADA CEDERA KEPALA
Penderita Cedera. Multipel dalam Koma
Resusitasi Cairan
TDS normal (>100 mm Hg)
Tidak terdapat tanda-tanda :- dilatasi pupil- refleks cahaya- hemiparesis
CT Scan kepala dan Abdomen
Terdapat tanda-tanda :
- dilatasi pupil- refleks cahaya -
- hemiparesis
CT Scan kepala
DPL/CT Abdomen
TDS abnormal (<100 mmHg)
DPL segera atau seliotomi(neurologis proritas yang kedua), bila dalam pembedahan timbul dilatasi pupil, pertimbangkan melakukan ventrikulografi
udara atau eksploratosi lubang bor, atau CT Scan setelah seliotomi.
Pada kasus borderline misalnya TDS dapat dikoreksi sementara tetapi cenderung untuk menurun, harts diupayakan memperoleh hasil CT Scan kepala sebelum penderita dibawa ke kamar operasi untuk seliotomi. Kasus seaport ini memerlukan keputusan klinis dan kerja sama yang balk antara ahli bedah trauma dan ahli bedah saraf.
Catatan Algoritme 3:
1. Semua penderita cedera kepala berat yang koma harus dilakukan resusitasi (ABCDE) saat tiba di UGD
2. TDS=Tekanan Darah Sistolik. Segera setelah TD normal, lakukan pemeriksaan mini neurologis (GCS & Reaksi cahaya pupil). Bila TD tidak dapat dinormalkan.
23
catat pemerksaan minineurologik dan tekanan darahnya.
3. Bila TDS tidak dapat diperbaild sampai diatas 100 nun Hg walaupun tclah dil resusitasi caimn secara agesif, prioritasnya sekarang adalah mencari pcnyebab hipote dan evaluasi neurosirurgis merupakan prioritas kedua. Pada kasus ini penderita dil DPL dan ultrasound di UGD atau langsung ke kamar operasi untuk seliotomy. Dan CT kepala dilakukan setelah seliotomy. Bila timbal tanda-tanda klinis suatu mass infra maka dilakukan ventrikulografi udara. Eksplorasi lubang bor atau craniotomy di operasi sementara seliotomy sedang berlangsung.
4. Bila TDS > 100 mm Hg setelah resusitasi dan terdapat gejala-gcjala suatu lesi intrakranial (pupil anisokor, hemiparesis) maka prioritas pertama adalah CT Scan k DPL dapat dilakukan di UGD, rang CT Scan atau kamar operasi namun evaluasi neurologi dan tindakan) tidak botch tertunda.
24
DAFTAR PUSTAKA
1. Advance Trauma Life Support, hal 196-235
2. Greenberg Michael I.2008.text-atlas of emergency medicine.Penerbit
Erlangga.Jakarta, hal 44-51
3. Netter FH, Machado CA. Atlas of Human Anatomy. Version 3. Icon Learning
System LLC, 2003
4. http://hubpages.com/hub/Cerebral_Hemorrhage_Kerala_shocking_fact
5. Satyanegara.Ilmu Bedah saraf. Penerbit EGC.Jakarta, hal 153-170
6. http://www.thecochranelibrary.com/userfiles/ccoch/file/CD001049.pdf
7. http://fhs.mcmaster.ca/surgery/documents/head_injury.pdf
8. Livingstone C. Neurology and Neurosurgery illustrated. Second edition. 1991
9. http://www.dokterbedahherryyudha.com/
25