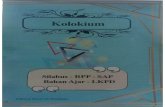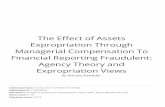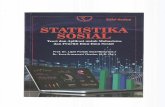Untitled - Unas Repository
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Untitled - Unas Repository
1
LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Peran Serikat Pekerja Dalam Membina Hubungan Industrial Pancasila Antara Pekerja,
Perusahaan dan Pemerintah di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang Timur
Tahun ke 2 (dua) dari Rencana 3 (tiga) tahun
TIM PENELITI
Ketua :
Dr.Drs.SIGIT ROCHADI,M.Si (0331125902)
Anggota :
ANGGA SULAIMAN, S.IP, MAP
UNIVERSITAS NASIONAL
November 2018
3
Ringkasan
Pembinaan hubungan industrial di Indonesia diharapkan dapat menciptakan ketenangan
kerja, lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang harmonis di kawasan industri
dimana para pekerja dan karyawan bekerja. Serikat pekerja sebagai perwakilan pekerja dan
manajemen sebagai perwakilan perusahaan memiliki peran penting dalam membina hubungan
industrial. Hubungan industrial berhasil dibina dengan baik melalui hubungan manajemen dengan
Serikat Pekerja dalam tahap akomodatif, kesejahteraan pekerja terjamin dan penghindaran aksi
mogok kerja. Serikat Pekerja berperan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, menyelesaikan
perselisihan dalam lembaga tripartit secara musyawarah dan mewadahi aspirasi pekerja sehingga
keinginan pekerja bisa dikoordinasikan yang berdampak pada terciptanya hubungan industrial yang
harmonis.
Permasalahan konflik sebaiknya dihindari dengan cara pihak Serikat Pekerja dan manajemen
agar saling bekerja sama dalam membina hubungan industrial. Hubungan industrial yang diharapan
berkembang di Indonesia berpedoman kepada nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila sehingga setiap
perusahaan di Indonesia diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan
aktivitas di lingkup industrial. Hubungan industrial yang berhasil dibina dengan baik oleh Serikat
Pekerja dan manajemen dengan menjadikan nilai-nilai bangsa sebagai pedoman dapat mewujudkan
lingkungan yang kondusif dan kondisi kerja yang harmonis. Hubungan industrial yang berpegang
pada nlai-nilai bangsa yaitu Pancasila diharapkan mampu mencapai peningkatan kesejahteraan
hidup pekerja, terpeliharanya ketenangan dalam bekerja dan berusaha sehingga berdampak pada
peningkatan hasil produksi (Sutedi, 2009: 37). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana
peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah dalam perlindungan pekerja agar tidak terjadi
PHK sepihak kemudian dalam penentuan upah minimum kabupaten dan pelaksanaannya dalam
konteks HIP, dalam penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) dan pelaksanaannya dalam
konteks HIP, mengapa kerja magang menjadi persoalan bagi pekerja definitive.
Kata Kunci: Peran Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial Pancasila
4
Prakata
Terimakasih kami ucapkan kepada Tuhan YME dan juga kepada rekan-rekan kolega FISIP
Universitas Nasional terutama Program Studi Sosiologi atas dukungan terhadap keberlanjutan dan
penyelesaian laporan kemajuan yang berjudul “Peran Serikat Pekerja Dalam Membina
Hubungan Industrial Pancasila Antara Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah di Kawasan
Industri Surya Cipta Karawang Timur. Tak Lupa kami memanjatkan doa bagi ketua tim
penelitian kami Almarhumah Ibu Dr. Anggraeni Primawati, M.Si yang telah meninggalkan kami
semua dan mewariskan optimism dan semangat dan perjuangan untuk menyelesaikan penelitian ini.
Serta dukungan selama proses penelitian berlangsung hingga akhir penulisan laporan ini yaitu dari
Ketua dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas
Nasional, Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si dan Adilita Pramanti, S.Sos, M.Si dan juga seluruh
kolega dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Nasional yang telah mendukung
penelitian ini hingga selesai dengan optimal.
Tujuan dari penelitian akhir ini adalah untuk mengetahui hubungan industrial Pancasila di
Indonesia diharapkan dapat menciptakan ketenangan kerja, lingkungan kerja yang kondusif dan
hubungan kerja yang harmonis di kawasan industri dimana para pekerja dan karyawan bekerja dan
mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila bagi stakeholders buruh, perusahaan dan pemerintah.
Kami berharap hasil laporan kemajuan kami ini dapat menambah referensi dan pengembangan
paradigma baru dalam hubungan industrial Pancasila saat ini di Indonesia.
Jakarta, November 2018
Tim Peneliti
5
Daftar Isi
Halaman Sampul ………………………………. 1
Halaman Pengesahan ……………………………….. 2
Ringkasan ……………………………….. 3
Prakata ……………………………….. 4
Daftar Isi ……………………………….. 5
Daftar Tabel ………………………………… 6
Daftar Gambar ………………………………… 7
Daftar Lampiran ………………………………… 8
Bab I Pendahuluan ………………………………… 9
Bab II Tinjauan Pustaka ………………………………… 18
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………… 42
Bab IV Metode Penelitian ………………………………… 45
Bab V Hasil dan Pembahasan …………………………………. 52
Bab VI Rencana Tahapan Berikutnya …………………………………. 56
Bab VII Kesimpulan dan Saran …………………………………. 57
DAFTAR PUSTAKA …………………………………. 59
LAMPIRAN
• instrumen
• personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya
• HKI dan publikasi
6
Daftar Tabel
1.3.1 Tabel Sistematika Laporan Kemajuan
4.2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Tipe Data
5.1 Tabel Capaian Luaran Penelitian Tahun Satu dan Tahun Dua
7
Daftar Gambar
Gambar 4.2.1 Tangga akses yang dibangun oleh peneliti
Gambar 4.3.1. Bagan Uji Keabsahan Data
Gambar 4.4.1 Bagan Strategi Analisis Data Tipe Ideal dan Hampiran Berturutan (successive
approximation)
5.1.1 Foto diskusi Proses penulisan Paper Internasional
5.1.2 Bukti Submit Jurnal Internasional
5 .2.1 Bukti online penerimaan makalah untuk pertemuan Ilmiah Nasional
6.1.1 Keikutsertaan dalam kongres dan Seminar Nasional Sosiologi
9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kebijakan keteganakerjaan
disusun dengan melibatkan secara penuh serikat-serikat pekerja. Kebijakan yang tertuang dalam
undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU13) memuat
secara lengkap aspek-aspek ketenagakerjaan. Dibanding kebijakan sebelumnya, misalnya undang-
undang No. 11 tahun 1988 dan undang-undang No. 25 tahun 1997, UU13 memiliki cakupan yang
luas, dalam dan posisi serikat pekerja demikian kuat. Hal ini dapat dipahami mengingat semangat
membentuk UU13 adalah semangat reformasi yang memangkas semua perlakuan istimewa negara
dan birokrasi terhadap buruh. Dalam hubungannya dengan serikat pekerja misalnya, pasal 102 ayat
2 UU13 menegaskan bahwa:
“Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan,
dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota
beserta keluarganya”.
Peranan serikat pekerja seperti dikemukakan di atas, masih dipertegas dalam undang-
undang nomer 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UUSP/B).
“Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh”. Penegasan ini
dimaksudkan untuk mencegah union busting yang sering terjadi pada masa Orde Baru. Tindakan
menghalang-halangi para buruh untuk berserikat dengan mengundang polisi bahkan tentara dalam
setiap perselisihan industrial, merupakan pengalaman traumatis. Dengan tidak adanya serikat
pekerja dalam suatu perusahaan atau serikat pekerja yang tidak genuine (benar-benar didirikan oleh
pekerja), perjanjian kerja bersama (PKB) terutama dalam pengupahan, cuti, kerja lembur, jaminan
kerja, tunjangan hari tua dan tunjangan keluarga, tidak berpihak kepada buruh. Oleh karena itu
UUSP/B menegaskan bahwa “perlunya pembentukan dan pengembangan serikat buruh yang bebas,
10
terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung-jawab, dan penegasan bahwa serikat buruh
merupakan sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan keluarganya”.
Butir-butir pasal dalam undang-undang yang dikemukakan di atas, menandai lahirnya era
baru hubungan industrial dari state centris ke labor oriented. Di era state centris, negara sangat
berkuasa menentukan semua hal yang berhubungan dengan buruh mulai upah, berserikat, fasilitas
kerja sampai pemogokan pun harus meminta ijin. Keluarnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
342/Men/1986 menunjukkan betapa besarnya kekuasaan negara yang dioperasikan oleh militer.
Dalam keputusan dimaksud, Menaker menyetujui intervensi militer jika muncul kasus hubungan
industrial. Tidak mengherankan jika muncul letupan di beberapa daerah industri di mana buruh
menolak campur tangan yang massif dari aparat keamanan. Kasus yang paling fenomenal adalah
penculikan dan pembunuhan aktivis buruh Marsinah tahun 19931. Kasus-kasus lain adalah
kekerasan di Medan tahun 1994, penangkapan dan penahanan aktivis buruh Muhtar Pakpahan,
pembubaran dan pelarangan Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBMS) (YLBHI, 1996, Rochadi,
1996, 1998), untuk menyebut beberapa contoh.
Kuatnya peranan militer dalam membangun hubungan industrial tidak dapat dilepaskan dari
strategi pembangunan yang dipilih Orde Baru. Sejak krisis keuangan negara pertengahan tahun
1980-an, Pemerintah mengubah strategi dari industrialisasi substitusi impor (ISI) ke industri
berorientasi ekspor (IOE) (Wie, 1992; Tambunan, 2012; Rochadi, 2014; Kuncoro, 2016). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang sebelumnya mengandalkan penjualan minyak bumi, beralih
ke ekspor komoditi baik hasil hutan maupun industri olahan. Konsekuensinya, pemerintah harus
menarik modal asing sebesar-besarnya. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara berkembang
lain, pemerintah Indonesia menjanjikan dua hal yaitu upah buruh murah dan keamanan serta
ketertiban (Rochadi, 1996, 1998, 1999). Janji pertama dipenuhi dengan penetapan upah buruh
dengan konsep upah minimum regional (UMR) berdasarkan Permenakertrans No. 1 Tahun 1999
1 Marsinah adalah buruh PT Catur Putera Surya yang memproduksi jam di Sidoarjo Jawa Timur. Pada tanggal 3 Mei 1993 ia memimpin pemogokan buruh yang menuntut kenaikan upah, tunjangan cuti haid, asuaransi kesehatan bagi buruh ditanggung perusahaan, THR satu bulan gaji sesuai dengan keputusan pemerintah, uang makan ditambah, kenaikan uang transport, bubarkan SPSI, tunjangan cuti hamil tepat waktu, upah karyawan baru disamakan dengan buruh yang sudah 1 tahun bekerja dan pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, PHK kepada karyawan yang menuntut haknya. Pada tanggal 9 Mei 1993 jazadnya ditemukan di hutan jati Wilangan Nganjuk Jawa Timur. Pengadilan yang berlangsung satu tahun dan telah menahan 9 orang karyawan mulai manajer sampai satpam PT CPS akhirnya membebaskan mereka dari tuduhan. Hingga kini pembunuh Marsinah belum ditemukan. Lihat ELSAM (1995), Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan: Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan yang Belum Terselesaikan. Jakarta: Elsam
11
tentang Upah Minimum dan Permenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang Perubahan
Permenakertrans No. 1 Tahun 1999. UMR merupakan upah minimum yang mencakup kebutuhan
fisik minimum di suatu daerah. Besarnya UMR ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Dewan
Pengupahan Daerah. Dengan upah minimum saja, para pengusaha yang mentaati hanya 72%,
sisanya membayar upah buruh di bawah UMR (Rochadi 1996, 1998). Terkait dengan janji pertama
ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempromosikan
upah buruh murah dan pasar potensial bagi calon-calon investor di luar negeri. Jumlah penduduk
yang besar dan tenaga kerja yang oversupply dipandang sebagai comparative advantage.
Janji kedua berupa keamanan dan ketertiban yang dipenuhi dengan melibatkan seintensif
mungkin militer dan polisi dalam menangani masalah perburuhan. Aparat keamanan berwenang
memberikan ijin atas pemogokan buruh, meskipun undang-undang menyatakan bahwa mogok
adalah hak buruh. Buruh tidak bisa menggunakan haknya karena tidak diijinkan oleh aparat
keamanan. Dalam kasus-kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), pelaksananya bukan kepala
human resources management (HRD), tetapi aparat keamanan. Tidak sedikit buruh yang akan di
PHK dipanggil ke KORAMIL dan diberi SK pemutusan hubungan kerja. Pendekatan keamanan
yang berarti militer dan polisi bertindak lebih dahulu untuk mewujudkan ketertiban, lebih
diutamakan dibanding dialog dan musyawarah. Kasus lain yang menonjol atas peran militer ini
adalah dalam pembentukan serikat pekerja baik di perusahaan maupun cabang-cabang. Di era Orde
Baru dianut state corporatism untuk mengendalikan kelompok-kelompok, sehingga dalam bidang
perburuhan hanya ada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pemerintah dan pengusaha
mencegah sedapat mungkin tidak ada serikat pekerja, tetapi jika buruh ingin membentuk serikat
harus mendapat persetujuan pemerintah (aparat keamanan). Karenanya semua pengurus SPSI
adalah orang-orang perusahaan yang telah mendapat persetujuan aparat keamanan.
Strategi seperti itu menunjukkan bahwa buruh tidak dikehendaki aktif dalam pembangunan.
Buruh diposisikan sebagai alat produksi yang mendapat pekerjaan berkat kebaikan pengusaha.
Sebagai alat produksi, buruh mudah disubstitusi dan jika perlu diganti. Hak buruh hanyalah upah
yang dibayarkan atas kehendak baik pengusaha. Memposisikan buruh seperti itu mengabaikan hak-
hak buruh seperti kebebasan berserikat (Konvenan ILO No. 87), berunding bersama (Konvenan
ILO No. 98) dan penghapusan diskriminasi upah (Konvenan ILO No. 100). Dampaknya adalah,
Indonesia dikucilkan dalam Sidang ILO di Genewa tahun 1994. Pemerintah Indonesia dinilai oleh
12
ILO terlalu banyak mencampuri buruh dan ketika Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara hendak
menyampaikan sambutan, ditolak oleh peserta sidang. Selain Cosmas bukan buruh dan tidak berhak
hadir dalam pertemuan, peserta sidang yang terdiri dari para aktivis buruh sedunia juga menilai
massifnya pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia. Selain itu, para aktivis buruh di Eropa dan
Amerika menyerukan untuk memboikot produk-produk Indonesia yang dipasarkan di negeri
mereka karena barang tersebut dihasilkan dengan melanggar hak-hak buruh.
Dalam konteks politik di mana pemerintah mendominasi seluruh aspek kehidupan
masyarakat2, hubungan industrial yang sejatinya hanya memerlukan kesepakatan pengusaha dan
pekerja menjadi sangat rumit. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk menegakkan prinsip-
prinsip hubungan industrial yang ditetapkannya dengan berpedoman pada dasar Negara dan
konstitusi. Namun konsep tripartite terlalu luas beroperasi sehingga konsep bipartite tidak berjalan.
Pemerintah Orde Baru memandang negatif kekuatan buruh (dan petani) dan memposisikannya
sebagai kekuatan kiri. Buruh dan petani selama berpuluh-puluh tahun memperoleh stigma negatif,
bagian dari pemberontak atau pelaku kudeta dan tidak loyal dengan Negara Indonesia. Karenanya
buruh harus terus dikontrol dan tidak diberi kesempatan mengorganisasi diri secara genuine.
Dalam perspertif semacam itu, hubungan industrial yang dibangun meskipun secara formal
disebut sebagai hubungan industrial Pancasila (HIP), dalam prakteknya sarat dengan koersi dan
eksploitasi buruh. Pemerintah mengekang hak-hak buruh, seperti hak berserikat, hak mendapat
upah yang layak, hak memperoleh jaminan sosial, hak cuti, hak mogok, hak membuat perjanjian
kerja bersama, dan hak mendapat perlindungan jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah lebih nyaman bekerjasama dengan pengusaha dibanding dengan buruh. Berbagai
keuntungan dapat diperoleh, misalnya para pejabat akan lebih mudah memperoleh pendapatan di
luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan
pribadi. Selain itu, melalui kekuasaan administrasi, para pejabat bisa mendapatkan kepemilikan
saham di perusahaan yang menjamin pendapatan para pejabat. Belajar dari hubungan khusus
Soeharto dan Liem Sioe Liong (Borsuk dan Cing, 2017), para pejabat di daerah khususnya militer
juga membina hubungan dengan para pengusaha. Mereka mengharapkan pendanaan dalam meniti
2 William Liddle berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru jauh lebih represif dibanding Negara-negara komunis.
Lihat hasil wawancara Anders Uhlin (1998) dan William Liddle (2002).
13
karir dan sebagai imbalannya, mereka akan menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan
pengusaha3.
Elit politik dan elit ekonomi bersatu, saling menopang dan mencapai cita-cita bersama
meskipun tujuannya berbeda. Dalam perspektif semacam itu, buruh yang kuat dianggap sebagai
penghalang. Meskipun industrialisasi selama Soeharto berkuasa tumbuh dengan pesat, tidak
berdampak pada kesejahteraan dan kekuatan buruh. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat
selama 30 tahun, tidak berpihak pada kebebasan, hak-hak asasi manusia apalagi kepada buruh.
Kelas menengah Indonesia memiliki ciri khusus sebagai kelas menengah berdarah biru. Mereka
yang menikmati kekayaan bukan karena kerja keras dan teruji kemampuannya menghadapi badai
kompetisi, tetapi kelas menengah yang lahir dari rahim birokrasi. Mereka mendapat perlakuan
khusus karena orang tuanya pejabat atau jenderal dan berbisnis dengan bantuan negara. Rata-rata
mereka mengerjakan proyek-proyek pemerintah, bukan menyemai produk tertentu kemudian
dipasarkan, menghadapi kompetisi kualitas produk dan harga, jatuh-bangun dan kemudian eksis
sebagai produsen barang tertentu yang menguasai pangsa pasar. Sebaliknya, mereka mendirikan
perusahaan untuk mengerjakan proyek pemerintah yang nilainya milyaran. Oleh karena control
masyarakat di era Soeharto dan media lemah, maka kualitas pekerjaan tidak menjadi perhatian.
Dengan kelas menengah semacam itu, tidak mungkin mengharapkan keberpihakannya terhadap
buruh.
Di antara Negara-negara yang belakangan melakukan industrialisasi, Indonesia belum
berhasil mendapatkan posisi dalam pembagian kerja internasional (international division of
labour). Investor asing di negeri kita paling leluasa bergerak, terutama mereka yang tidak
membangun industri dengan rangkaian teknologi yang kuat (footloose). Ancaman akan
hengkangnya investor terus dikemukakan jika muncul kasus-kasus perburuhan. Vietnam dan
Thailand sering dirujuk sebagai tujuan pemindahan (relokasi) industri yang tenaga kerjanya dinilai
memiliki skill lebih baik dan lebih disiplin. Kondisi ini diperparah dengan oversupply tenaga kerja,
di mana satu lowongan kerja di sektor formal diperebutkan oleh empat pencari kerja. Sedangkan
upaya penciptaan lapangan kerja dikalkulasi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap satu persen
3 Jenderal Gatot Nurmantyo mantan KSAD dan penglima TNI juga menempuh cara yang dilakukan Soeharto. Ia
menjalin hubungan khusus dengan pengusaha Tomy Winata ketika pangkatnya masih letnan. Tomy-lah yang
mendukung pendanaan Gatot dalam meniti karir dan berencana membiayai jika Gatot mencalonkan sebagai presiden
2019. Lihat majalah Tempo 2 April 2018.
14
pertumbuhan ekonomi, diperkirakan membuka lapangan kerja 300 ribu orang (Tabloid Kontan, 5
Mei 2014). Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5 persen per tahun berarti hanya tercipta 1,650
juta setiap tahunnya. Padahal lulusan sekolah lanjutan atas (SMA dan SMK) sekitar 2,5 juta orang
(Tempo, 13 Agustus 2013). Dengan tambahan sekitar 500 ribu orang yang kuliah, maka terdapat
pengangguran terbuka sebesar 350 ribu orang tiap tahun.
Didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan di tengah persaingan yang terus
meningkat, maka buruh dihadapkan pada berbagai persoalan. Pertama, mempertahankan pekerjaan
yang telah diperoleh, jika mungkin menaikkan status menjadi pekerja tetap. Outsorcing, kerja
kontrak dan magang diterima untuk sementara, tetapi tujuan utama pekerja adalah melindungi diri
mereka dari ancaman PHK setiap saat. Kedua, upah yang sesuai dengan keputusan bupati atau
walikota yang dikenal sebagai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Untuk sektor padat modal,
sebagian besar pengusaha telah memenuhi UMK, sebaliknya di sektor padat karya upah buruh
masih di bawah UMK. Seringkali upah dibayarkan setelah dua bulan berjalan4. Kondisi ini diterima
pekerja karena mereka tidak punya pilihan. Ketiga, penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB)
yang isinya dan pelaksanaannya diketahui oleh buruh. Pengusaha kurang bersemangat membuat
PKB, selain di setiap perusahaan terdapat beberapa serikat buruh yang menyulitkan
penyusunannya, PKB kurang leluasa bagi pengusaha5. Keempat, status magang digunakan sebagai
modus oleh pengusaha untuk mendapatkan pekerja muda, murah dan produktif. Setelah isu
oursourcing agak mereda (bukan hilang), program Kementrian Tenaga Kerja yang mewajibkan
setiap perusahaan membuka kesempatan magang bagi lulusan sekolah lanjutan atas baik SMA
maupun SMK6, menimbulkan masalah di lapang.
Dengan dalih pemagangan, maka perusahaan-perusahaan memperoleh tenaga kerja
produktif dan murah. Pasalnya mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dengan buruh/pekerja
4 Di Karawang pekerja tekstil dan produk tekstil (TPT) dibayar dibawah UMK. Upah bulan Januari diterima bulan
Maret. Pengusaha sector ini telah membuat laporan kepada Dinas Tenaga Kerja akan ketidakmampuannya membayar
upah sesuai UMK. Pengusaha menyerahkan kepada pemerintah jika mau menjual asetnya, tetapi jika tetap diijinkan
berjalan, pengusaha minta diijinkan membayar upah sesuai kemampuan (Wawancara dengan Suroto Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Karawang dan Agus Ketua Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/ SPSI Cabang
Karawang di Karawang tanggal 12 Juli 2018). 5 Di Karawang terdapat 542 perusahaan dan hanya sekitar 20% yang telah memiliki PKB. Sebagian besar perusahaan
di Karawang menjalankan peraturan perusahaan (PP). Menurut UU13, PKB adalah perjanjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Penyusunan
PKB memerlukan keterlibatan dan persetujuan serikat pekerja. Sedangkan PP adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis oleh perusahaan yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja dan tata-tertib perusahaan. 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
15
biasa tetapi dibayar dengan upah murah. Telah timbul gejala di mana pengusaha lebih tertarik
merekrut tenaga magang dengan hanya memberi uang transport dan mengerjakan pekerjaan yang
sama dengan pekerja tetap atau kontrak. Pekerja magang jelas tidak bisa masuk serikat, sehingga
jumlah anggota serikat buruh terus menurun demikian pula jumlah serikat buruh. Jika pada tahun
2007 jumlah serikat buruh sekitar 14.000 dan jumlah anggota sekitar 3,4 juta orang, tahun 2017
serikat buruh tinggal 7.000 dengan anggota sekitar 2,7 juta orang (Pernyataan Menteri Tenaga
Kerja Hanif Dakhiri seperti dikutip https://www.cnnindonesia.com tanggal 29 Maret 2018). Pada
hal pada tahun 2017 jumlah pekerja di sektor formal mencapai 52 juta orang (www.bps.go.id
tanggal 23 September 2017), sehingga jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja hanya
5,1%.
Dengan memahami konteks sosial ekonomi di mana serikat buruh dibentuk dan
menjalankan perannya, studi ini akan fokus pada peranan serikat buruh dalam membangun
hubungan industrial Pancasila. Topik terakhir ini diangkat kembali pasca Orde Baru karena
massifnya konflik industrial di kawasan industri sejak awal tahun 2000 hingga akhir-akhir ini.
Konflik industrial seakan mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan cenderung mengarah pada tarik
menarik kepentingan berdasarkan kekuatan. Tidak sedikit pengusaha yang memobilisasi preman,
jawara atau tokoh-tokoh lokal. Sedangkan para buruh juga cenderung mengandalkan kekuatan fisik
(jumlah buruh) dean melakukan pendudukan dan penguasaan tempat-tempat umum, seperti pabrik
dan jalan raya. Apalagi tumbuh serikat-serikat buruh dengan tujuan yang menyimpang dari
Pancasila, baik serikat buruh kedaerahan maupun serikat buruh keagamaan. Mereka ini
memanfaatkan ruang demokrasi, meskipun tujuannya bertentangan dengan demokrasi.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah bersikap mendua. Pemerintah secara jelas
menunjukkan sikap tidak tegas dan kehilangan pegangan karena “keras terhadap buruh”, takut
kehilangan suara/ dukungan dan “keras terhadap pengusaha” takut kehilangan sumberdaya
ekonomi. Akibatnya, pemerintah bersikap menunggu laporan dari serikat buruh jika terjadi
pelanggaran dan tidak proaktif melakukan kunjungan ke perusahaan, berdiskusi degan serikat-
serikat buruh untuk menjembatani perbedaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Posisi sebagai
mediator tidak mungkin dijlankan dengan sikap pasif, alih-alih mempromosikan konsep hubungan
industrial Pancasila sebagai pedoman baik bipartite maupun tripartite. Tidak mengherankan jika
16
hubungan industrial yang berlangsung dipenuhi permusuhan akut antara serikat buruh dan
pengusaha dengan masalah yang silih berganti.
1.2 Masalah Penelitian
Dengan memahami latar belakang masalah di atas, minimal ada 4 (empat) persoalan
hubungan industrial, yaitu kondisi angkatan kerja yang oversupply sehingga pekerja dalam posisi
lemah. Kemudian masalah upah buruh yang tidak seluruhnya dibayar sesuai UMK, dominannya PP
dan bukan PKB sebagai pedoman tertulis di perusahaan dan mulai membesarnya tenaga kerja di
perusahaan dengan status ‘magang”. Keempat aspek ini harus diletakkan dalam kontek hubungan
industrial Pancasila (HIP) karena seluruh tatanan kehidupan termasuk hubungan industrial harus
merupakan penerjemahan dasar negara Pancasila. Dengan demikian, pertanyaan utama yang perlu
dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana peranan serikat pekerja, manajer perusahaan dan
dinas ketenagakerjaan kabupaten Karawang dalam membina hubungan industrial Pancasila di
kawasan industri Surya Cipta Karawang Timur?
Secara khusus, penelitian ini hendak mendeskripsikan fenomena di lokasi penelitian hal-hal
sebagai berikut:
a. Bagaimana peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah dalam perlindungan
pekerja agar tidak terjadi PHK sepihak?
b. Bagaimana peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah dalam penentuan upah
minimum kabupaten dan pelaksanaannya dalam konteks HIP?
c. Bagaimana peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah dalam penyusunan
perjanjian kerja bersama (PKB) dan pelaksanaannya dalam konteks HIP? Mengapa PP
lebih dipilih oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industry Karawang Timur?
d. Mengapa kerja magang menjadi persoalan bagi pekerja definitive? Jika magang
merupakan tahapan untuk mengintegrasikan pendidikan dan pekerjaan, bagaimana
strategi pemerintah mewujudkan kepastian kerja bagi pekerja di kawasan industri
Karawang Timur?
17
1.3 Sistematika Laporan
Laporan Kemajuan Penelitian
HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN
BAB 4. METODE PENELITIAN
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI
BAB 6. RENCANA TAHAPAN
BERIKUTNYA
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
• Artikel ilmiah (draft, bukti status
submission atau reprint), jika ada.
• Produk penelitian
1.3.1 Tabel Sistematika Laporan Kemajuan
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini tentang peranan serikat pekerja dalam membina hubungan industrial Pancasila
di kawasan industri Karawang Timur. Penelitian ini bermaksud mesdeskripsikan peranan serikat
pekerja, bagian manajerial perusahaan dan dinas ketenagakerjaan kabupaten Karawang dalam
membina hubungan industrial Pancasila. Memperhatikan tujuan penelitian tersebut, maka konsep-
konsep yang harus ditelaah adalah peranan serikat pekerja, hubungan industrial dan hubungan
industrial Pancasila. Oleh karena penelitian sosial tidak mungkin dipisahkan dari konteks, maka
konteks sosial baik lokal maupun nasional perlu dikemukakan. Konteks dimaksud adalah
industrialisasi, kondisi ekonomi dan politik yang merupakan ruang sosial di mana hubungan
industrial berlangsung. Globalisasi ekonomi yang mempengaruhi sikap pengusaha dalam
berinvestasi, melakukan relokasi dan mempengaruhi serikat-serikat buruh yang pada akhirnya
mempengaruhi posisi tawar Negara dan pengusaha, akan disinggung sebagai lingkungan global.
2.1. Para Pemikir Awal Hubungan Industrial
Hubungan industrial berawal dari revolusi industri di Inggris akhir abad 18. Revolusi ini
secara perlahan-lahan melahirkan kelas baru yaitu kelas buruh (pekerja) upahan yang
mengandalkan tenaganya. Hubungan kerja dalam struktur masyarakat feodal yang ditandai dengan
kesepakatan-kesepakatan lisan, berubah menjadi kesepakatan tertulis, meskipun di Inggris
perubahan itu baru berlangsung satu abad kemudian (Perry, 2013). Sebelum benar-benar menjadi
masyarakat industri, di Inggris (dan Jerman) berkembang industri rumahan yang mempekerjakan
beberapa orang. Antara pemilik usaha dan pekerja juga terikat kesepakatan kerja secara lisan.
Operasionalisasi dari usaha-usaha semacam ini diawasi oleh gilda (guild), sebuah kelompok yang
anggota-anggotanya terdiri dari pedagang dan pengrajin yang mengontrol pelaksanaan pekerjaan di
wilayahnya (Schneider, 1986).
Transisi dari masyarakat feodal ke industri merupakan lahan subur bagi kajian sosial
politik, khususnya hubungan industrial dan gerakan sosial (Rochadi, 2008). Beberapa pemikiran
awal lahir dari konteks sosial ini seperti pemikiran Marx, Durkheim dan Weber. Karl Marx adalah
peletak dasar studi hubungan industrial, meskipun ia tidak pernah menggunakan kata tersebut
19
dalam analisisnya. Hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang dalam pemikirannya
merupakan konflik untuk menguasai satu dari yang lain, adalah premis utama teori Marx.
Masyarakat industri yang menurut Marx disebut masyarakat kapitalis, dengan demikian
membangun hubungan industrial yang antagonis. Kapitalis sebagai pemilik modal berupaya meraih
keuntungan seoptimal mungkin dengan upah buruh yang sesuai dengan harga pasar dan kondisi
kerja yang terbatas untuk mendukung akumulasi capital, sedangkan para pekerja yang secara terus
menerus dieksploitasi berusaha mengambil alih kepemilikan modal dan memimpin perubahan
sosial di masyarakat.
Teori hubungan industrial Marx diletakkan dalam konteks nilai tenaga kerja, nilai lebih
dan laba. Seluruh konsep tersebut dalam rangka hubungan pemilik modal dengan pekerja. Nilai
tenaga kerja, sama seperti nilai setiap komoditi, ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk
menciptakannya (Laeyendecker, 1983; Magnis-Suseno, 2000). Dengan demikian, nilai tenaga kerja
adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup, artinya dapat
memulihkan tenaga dan memperbarui dan menggantikannya jika ia sudah tidak dapat bekerja lagi
(Magnis-Suseno, 2000). Untuk memenuhi hal tersebut, buruh harus mendapat upah yang senilai
dengan apa yang diberikannya. Dengan mekanisme ini, maka tercipta “keadilan” di mana upah
buruh menunjukkan pertukaran setara (ekuivalen). Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup
satu hari mulai dari makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan keluarga, seorang buruh
memerlukan 50 ribu rupiah, maka sebesar itu pula upah yang diterima buruh. Itulah nilai tenaga
kerja buruh.
Argumen di atas akan lebih jelas jika dilengkapi dengan konsep nilai lebih. Tenaga kerja
yang dibeli oleh majikan seharga 50 ribu rupiah tersebut seluruhnya dikuasai oleh majikan dan
digunakan bekerja untuk majikan. Lamanya buruh bekerja tergantung majikan. Dalam hubungan
industrial klasik rata-rata lama kerja buruh 12 jam, kemudian berubah menjadi 10 jam dan di era
post industri rata-rata 8 jam sehari. Dengan waktu tersebut, ternyata buruh mampu menghasilkan 75
ribu rupiah per hari. Ada selisih 25 ribu rupiah per hari yang menjadi milik majikan. Seharusnya
buruh hanya bekerja 5 jam lewat sedikit untuk memperoleh hasil setara 50 ribu rupiah. Sisa 2 jam
kerja dengan nilai 25 ribu rupiah ini menjadi milik majikan dan disebut nilai lebih. Nilai lebih
inilah yang merupakan laba kapitalis dan laba perusahaan seluruhnya tergantung dari besar kecilnya
nilai lebih. Dalam sistem kapitalis yang bertumpu pada konsep harus menghasilkan keuntungan
dari kerja para buruh, pelipatgandaan modal berjalan dengan cepat. Di sisi lain, upah buruh selalu
20
lebih rendah dari nilai tenaga kerja, maka kapitalisme menciptakan ketimpangan kaya-miskin yang
sangat lebar. Dengan semakin besarnya modal yang diperoleh, kapitalis yang kuat memenangkan
persaingan dan terjadilah akumulasi modal di tangan segelintir orang. Sedangkan jumlah proletariat
semakin bertambah karena para pengusaha kecil dan wiraswastawan lama-lama mati kalah beraing
dengan industri besar. Selain ketimpangan yang semakin meruncing, kemelaratan juga semakin
meluas.
Untuk bisa merebut modal, para pekerja harus membangun kekuatan diri. Mula-mula
mereka membangun komunikasi dalam suatu pabrik tempat mereka bekerja untuk menumbuhkan
kesadaran kelas (class consciousness). Kesadaran kelas tahap ini masih merupakan class in its self
yang belum mampu membangun kekuatan untuk menghadapi kelas borjuis (Laeyendecker, 1983).
Class in its self belum merupakan satu kesatuan, meskipun dalam proses produksi mereka telah
menyadari posisinya sebagai kaum proletar. Berkat perkembangan teknologi khususnya media
komunikasi, mereka mampu mengorganisasi diri secara nasional. Proses penyatuan yang semakin
meningkat ini walaupaun masih menghadapi konflik-konflik internal dan banyak mengalami
kekalahan, tetapi dukungan pedagang kecil, industri kecil dan terutama intelektual kota, turut
mendorong tumbuhnya kesadaran politik kaum proletar bukan hanya posisinya dalam proses
produksi tetapi juga penindasan yang hebat dan berkelanjutan dari borjuasi serta kesadaran
menyeluruh untuk menghentikan penindasan. Inilah momen yang oleh Marx disebut kesadaran
kelas yang nyata atau class for its self (kelas bagi dirinya sendiri). Jadi bagi Marx, bukan kesadaran
manusia yang menentukan kesadaran mereka, tetapi kesadaran sosiallah yang menentukan
kesadaran mereka (Magnis-Suseno, 2000).
Mengingat kepentingan dasar kedua kelas yang bertolak belakang, maka keduanya tidak
mungkin bersatu. Mengharapkan hubungan industrial yang harmonis dalam masyarakat kapitalis
merupakan impian yang tidak mungkin terwujud. Karena kelas borjuis sekaligus penguasa yang
mengontrol kelas buruh, perubahan hubungan industrial merupakan hasil pertentangan antara kedua
belah pihak. Pemilik modal secara terus menerus berusaha untuk memaksimalkan keuntungan
(laba), sementara buruh berusaha untuk meningkatkan upah dan kondisi kerja. Baik struktur,
substruktur maupun institusi-institusi yang lahir merupakan hasil pergulatan antara kelas borjuis
dengan kaum proletar. Penindasan yang satu terhadap lainnya hanya bisa dihentikan jika
kepemilikan pribadi dihilangkan.
21
Pemikiran Durkheim berbeda cukup jauh dengan Marx, meskipun keduanya bertolak dari
konteks sosial yang sama, yaitu masyarakat industri. Bagi Durkheim hubungan industrial
merupakan fakta sosial baik dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis maupun solidaritas
organis. Fakta sosial adalah struktur-struktur sosial, norma sosial dan nilai-nilai kultural yang
eksternal bagi dan bersifat memaksa kepada para actor (Ritzer, 2014) dan masyarakat tentunya.
Hubungan industrial pada masyarakat dengan solidaritas mekanis dapat berupa norma sosial dan
nilai-nilai kultural yang membentuk dan memediasi buruh dengan pengusaha. Sebaliknya, pada
masyarakat dengan solidaritas organis hubungan industrial mewujud dalam birokrasi, berbagai
kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan perusahaan, institusi pemerintah khususnya yang
menangani perburuhan dan industri, struktur perusahaan, serikat buruh, bipartite, tripartite dan
sebagainya. Hubungan industrial dalam perspektif Durkheim bersifat eksternal dan memaksa,
artinya seluruh tatanan sosial yang mengatur hubungan antara buruh dan majikan berada di luar
individu-individu, dan memaksa para individu tersebut untuk menaatinya7.
Dalam The division of labour, Durkheim menjelaskan terjadinya transformasi masyarakat
dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas
mekanis bersatu karena semua orang generalis. Ikatan di antara anggota-anggota masyarakat adalah
kesamaan atau kemiripan. Aktivitas mereka sehari-hari mirip demikian pula tanggung jawabnya.
Sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan, oleh
adanya fakta bahwa masing-masing mempunyai pekerjaan dan tanggung awab yang berbeda
(Ritzer, 2014). Transformasi demikian lazim terjadi dari masyarakat pedesaan (pertanian) ke
masyarakat perkotaan (industri). Durkheim tidak tertarik membahas konflik-konflik dalam proses
transformasi tersebut, sebaliknya ia justru membahas panjang lebar tentang integrasi. Penyebab
peralihan dari solidaritas mekanis ke solidaritas dinamis adalah kepadatan dinamis. Konsep ini
digunakan oleh Durkheim untuk menjelaskan jumlah orang dalam suatu masyarakat dan jumlah
interaksi di antara mereka. Semakin banyak orang akan semakin meningkat kompetisi dan semakin
banyak interaksi berarti perjuangan lebih keras di antara mereka untuk bertahan hidup (Ritzer,
2014). Jadi masyarakat dengan solidaritas organik dicirikan oleh spesialisasi berdasarkan keahlian,
7 George Ritzer mempertanyakan, bagaimana mungkin fakta non material seperti nilai-nilai kebudayaan bersifat
eksternal bagi sang actor? Pada hal sumber dari kebudayaan adalah ide-ide yang melekat dalam diri actor. Dalam hal
ini Durkheim menjawab bahwa pada awalnya fakta social non material ditemukan dalam pikiran para actor. Tetapi
ketika manusia berinteraksi demikian kompleks, interaksi tersebut akan mengikuti hukum-hukum yang dimiliki
bersama. Lihat selengkapnya Ritzer (2014:132).
22
ketergantungan antar anggota, consensus, kompetisi, kelangkaan barang, kerja keras anggota-
anggotanya dan interaksi yang kompleks.
Durkheim menempatkan moralitas sebagai pondasi disiplin ilmu (sosiologi). Hal ini
menempatkannya sebagai sosiolog yang unik, yaitu sosiologi yang diarahkan untuk mempelajari
moralitas sebagai struktur sosial, proses pembentukan struktur, posisi moralitas dalam struktur
sosial, bagaimana moralitas dilembagakan dan bagaimana kesehatan moral diupayakan dalam
masyarakat. Oleh sebab itu ketimpangan sosial, tindakan aktor atau institusi yang melanggar nilai-
nilai sosial dan moralitas masyarakat, mendapat kecaman Durkheim. Dengan demikian, penindasan
majikan terhadap buruh yang dideskripsikan Marx, tidak dapat ditoleransi dalam pikiran Durkheim.
Meskipun antara majikan dan buruh ada kompetisi karena kepadatan dinamis, antar keduanya harus
ada konsensus dengan membentuk struktur sosial yang disepakati dan mengikat secara bersama-
sama. Peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berbagai kebijakan pemerintah
dalam bidang ketenagakerjaan dan industri, merupakan struktur sosial yang memaksa dan mengikat
buruh serta majikan.
Max Weber (1864-1920), sosiolog kelahiran Jerman juga tidak secara khusus membahas
hubungan industrial, tetapi pemikirannya menjadi pondasi perkembangan ilmu sosial termasuk
sosiologi industri. Konsep-konsep yang dicetuskan oleh Weber untuk pembentukan hubungan
industrial adalah tindakan sosial, otoritas, rasionalisasi dan spirit kapitalisme. Untuk analisis sosial,
Weber membedakan tindakan sosial dan perilaku reaktif semata-mata. Dikatakan tindakan sosial
jika individu-individu yang terlibat memaknai tindakan tersebut. Atau tindakan sosial adalah
tindakan yang memiliki makna, tujuan atau motif subjektif. Contoh yang diberikan Weber adalah
tindakan ekonomi yang didefinisikan sebagai “orientasi yang sadar, terutama kepada pertimbangan
ekonomi. Masalah yang penting bukan kebutuhan objektif untuk membuat persediaan ekonomi,
tetapi kepercayaan bahwa hal itu perlu (Ritzer, 2014). Dalam teori tentang tindakan sosial ini secara
jelas Weber menempatkan individu sebagai unit analisis, pola-pola dan regularitas tindakan dan
bukan pada kolektivitas. Inilah sebabnya mengapa Weber juga menjadi tokoh dalam studi
psikologi.
Ada tiga tindakan sosial, yaitu tindakan rasional, tindakan afektif dan tindakan tradisional.
Tindakan rasional oleh Weber dibedakan menjadi rasionalitas instrumental (alat –tujuan) atau
tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam
lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan-pengharapan tersebut merupakan alat untuk
23
mencapai tujuan yang diperhitungkan secara rasional. Kedua adalah rasioalitas nilai yaitu tindakan
yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang etis,
estetis, religius atau bentuk lainnya, terlepas dari prospek keberhasilannya (Ritzer, 2014). Di
samping tindakan rasional, Weber juga menyebutkan tindakan afektif yang ditentukan oleh keadaan
emosi aktor. Sedangkan tindakan tradisional ditentukan oleh cara-cara berperilaku sang aktor yang
biasa dan lazim.
Sumbangan penting lainnya dari Weber adalah konsep tentang otoritas. Weber melakukan
analisis atas struktur-struktur otoritas dengan menunjukkan dominasi, yaitu probabilitas bahwa
perintah-perintah spesifik atau seluruhnya akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu. Dari
berbagai bentuk dominasi, Weber paling tertarik pada dominasi yang sah yang disebutnya otoritas.
Ada tiga basis yang menandai otoritas yaitu legal-rasional, tradisional dan karismatik. Otoritas legal
rasional bersandar pada aturan-aturan yang ditetapkan, pada keputusan yang sah dari suatu lembaga
baik private maupun publik. Otoritas tradisional bertumpu kepada kepercayaan yang telah
berlangsung demikian lama melalui proses interaksi, pada kesucian tradisi dan legitimasi orang-
orang yang melaksanakan perintah menurut tradisi. Sedangkan otoritas karismatik bersandar pada
kesetiaan pengikut terhadap pemimpin yang diakui memiliki kesucian luar biasa, watak, teladan,
horoisme (kepahlawanan) dan kemampuan istimewa.
Otoritas legal-rasional dapat mengambil bentuk-bentuk yang bermacam-macam, tetapi
Weber memberi perhatian kepada birokrasi yang dia anggap sebagai tipe pelaksanaan otoritas yang
paling murni. Dibanding bentuk lainnya, birokrasi mememiliki kelebihan-kelebihan, yaitu:
a. Birokrasi mampu mencapai derajad efisiensi tertinggi.
b. Birokrasi merupakan alat yang paling rasional bagi pelaksanaan otoritas kepada umat
manusia.
c. Birokrasi lebih unggul dibanding otoritas lain terutama dalam presisi, stabilitas, disiplin
dan kehandalan pekerjaan.
d. Birokrasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis pekerjaan administrasi.
Berbagai keunggulan tersebut dimiliki birokrasi karena otoritas ini memiliki sifat-sifat utama yang
tipikal, yaitu:
1. Ia terdiri dari pengaturan kesinambungan fungsi-fungsi resmi (jabatan-jabatan) yang
dibatasi oleh aturan-aturan.
24
2. Tiap jabatan mempunyai lingkup kompetensi khusus. Jabatan mengusung seperangkat
kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi, otoritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi
itu dan alat-alat pemaksa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu.
3. Jabatan-jabatan diorganisasi ke dalam suatu sistem hirarkies.
4. Jabatan-jabatan dapat menetapkan syarat-syarat kualifikasi teknis yang mengharuskan
para peserta mendapatkan pelatihan yang sesuai.
5. Staf yang mengisi jabatan itu tidak mempunyai alat produksi yang berkaitan dengan
mereka. Para anggota staf dilengkapai dengan alat-alat yang mereka butuhkan untuk
melakukan pekerjaan itu.
6. Pemangku jabatan tidak diijinkan memanfaatkan posisi, dia senantiasa merupakan bagian
organisasi itu.
7. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dan aturan-aturan administratif dirumuskan dan
direkam secara tertulis.
Tetapi tidak sedikit kelemahan terhadap birokrasi. Weber menyebut dua hal penting yaitu kekakuan
birokrasi atau yang sering disebut pita merah (red tape) dan sering membuat warga kesal dan
prosedur yang berbelit-belit. Selain itu rasionalisasi yang mendominasi semua aspek kehidupan
birokrasi adalah ancaman bagi kemerdekaan individu. Meskipun demikian, birokrasi sebagai
lembaga yang tidak dapat dielakkan (escape proof) dan sekali terbentuk sulit dihancurkan. Dalam
masyarakat modern, birokrasi merupakan pilihan utama. Jika tidak, maka yang ada pekerjaan
amatir.
Dalam menganalisis perkembangan kapitalisme, Weber menghubungkan pada etika
protestan, khususnya Calvinisme. Ajaran Calvin tidak menolak dunia dan tidak focus pada
asketisme, tetapi mendesak secara aktif para anggotanya untuk bekerja dalam dunia agar mereka
dapat menemukan keselamatan atau minimal tandak-tandanya (Ritzer, 2014). Para anggota gereja
dimotivasi untuk menolak segala sesuatu yang tidak etis, estetis atau tergantung pada reaksi-reaksi
emosional mereka pada dunia sekuler. Ajaran Calvin ini memotivasi para jemaat untuk hidup
disiplin, rasional, terbuka, dan hemat. Dalam pandangan Weber, ajaran Calvin ini memberi
semangat (spirit) yang istimewa yang pada akhirnya membuat ekonomi rasional. Weber tidak
menerangkan semangat kapitalisme dengan ketamakan ekonomi, justru sebaliknya sistem moral,
etis dan suatu etos. Menjadikan pengejaran keuntungan menjadi suatu etos itulah yang penting
dalam pertumbuhan kapitalisme di Barat. Di sini ditekankan, Protestanisme bukan penyebab
25
bangkitnya kapitalisme, tetapi membentuk etos umatnya untuk hidup rasional, disiplin, bekerja
sistematis, tidak sepenuhnya asketisme dan menekuni profesi. Melalui etos ini terbangun system
ekonomi yang secara terus menerus bergerak maju, berlangsung pertumbuhan ekonomi,
2.2. Perkembangan Konsep dan Teori Hubungan Industrial
Studi terhadap hubungan industrial berkembang pesat, bukan hanya cakupannya tetapi
juga pendekatan-pendekatannya didorong oleh pesatnya industrialisasi. Arena ini silih berganti
menunjukkan kekuatan pengusaha, serikat pekerja maupun pemerintah. Hubungan industrial
merujuk pada hubungan antara pengusaha, pekerja, manajer perusahaan, serikat-serikat pekerja,
organisasi-organisasi pengusaha dan pemerintah. Oleh karena arena hubungan dipengaruhi oleh
system sosial, budaya dan politik, maka hubungan industrial juga dibentuk oleh system sosial dan
system politik. Sistem sosial yang terbuka dan system politik yang demokratis, cenderung
membentuk hubungan industrial yang demokratis. Demikian pula, system politik yang otoriter,
kaku dan system sosial yang tertutup juga cenderung membentuk system hubungan industrial yang
otoriter.
Selain industrial relation, digunakan istilah labour relation. Penggunaan istilah terakhir
ini lebih menunjukkan hubungan kerja di perusahaan/ pabrik antara pekerja (serikat pekerja)
dengan pengusaha. Pada awalnya hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah antara
pekerja/buruh dan pengusaha. Ini sejalan dengan pandangan ekonomi klasik di mana mekanisme
pasar sebagai tumpuan. Dalam mekanisme pasar hanya ada penjual dan pembeli. Jika sebuah pasar
berhasil memenuhi kebutuhan pribadi dari semua pelaku di dalamnya, maka pasar juga telah
memenuhi kebutuhan manusia dan tujuan sosialnya. Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika
individu-individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual (Caporaso dan
Levine, 2016). Ekonomi klasik berasumsi semua orang sebagai pelaku ekonomi yang aktif. Dia
produsen sekaligus konsumen, sehingga system pertukaran akan berlangsung secara alami sehingga
keadilan lebih mudah terwujud.
Dalam ekonomi modern konsep yang digunakan industrial relation untuk merujuk pada
hubungan pelaku-pelaku industri, bukan hanya buruh dan pengusaha tetapi juga pemerintah melalui
kebijakan-kebijakannya. Seperti dikemukakan oleh Musgrave & Musgrave (1994) dalam
perekonomian modern, pemerintah perlu intervensi. Jenis dan luasnya intervensi tergantung pada
masalah yang dihadapi. Secara umum fungsi pemerintah dalam perekonomian adalah distribusi,
26
stabilisasi dan alokasi. Ketiga fungsi ini digunakan secara bersamaan untuk mendorong
berfungsinya mekanisme pasar yang tidak eksploitatif di mana pemilik modal besar cenderung
mematikan yang lemah.
Di Negara-negara industri, hubungan industrial diserahkan kepada kesepakatan buruh dan
majikan. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka pemerintah campur tangan yang bertujuan untuk
mencegah ketidakadilan. Dari tesis tersebut mengemuka pertanyaan, apakah peranan Negara? Jika
Negara campur tangan dalam urusan buruh dengan pengusaha, bagaimanakan campur tangan
tersebut dilakukan? Apakah sebaiknya buruh dan majikan dibebaskan membangun kesepakatan
kerja sama karena mereka tahu yang terbaik bagi mereka? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
lahirlah beberapa konsep dan teori, yaitu hubungan industrial kapitalis, hubungan industrial sosialis,
teori kelembagaan dan teori hubungan industrial Pancasila. Teori-teori tersebut secara ringkas akan
dikemukakan di bawah ini.
2.2.1. Teori Hubungan Industrial dalam Perspektif Kapitalis
Tidak ada istilah yang paling kontroversal di dunia akademik juga di kalangan pergerakan
Indonesia, selain kapitalisme. Ahli ekonomi Lucien Febre, Seligman dan Cassel, mengutuk istilah
tersebut dan memintanya untuk disingkirkan dari diskusi akademik. Sedangkan tokoh-tokoh
pergerakan seperti Tjokroaminoto, Soekarno dan Syahrir menyebutnya sebagai zondig atau jahat.
Tidak mengherankan jika para tokoh pergerakan di Dunia Ketiga lebih nyaman dengan pikiran
sosialisme. Konsep terakhir ini berakar dan berkembang kuat di Indonesia karena memiliki akar
kuat, yaitu system sosial Indonesia dengan gotong royong, arisan, tolong-menolong, mayoritas
penduduk Indonesia penganut Islam dan kuatnya pengaruh ajaran Karl Marx di kalangan
pergerakan kemerdekaan (Mintz, 2012).
Kapitalisme dengan berbagai variannya, minimal memiliki tiga ciri penting yaitu
pemilikan, persaingan dan rasionalitas. Semua system kapitalisme mengijinkan kepemilikan pribadi
bahkan sampai tidak terbatas. Di Indonesia ada pembatasan pemilikan tanah menurut undang-
undang No. 5 tahun 1960, tetapi tidak berjalan. Penguasaan tanah justru di tangan pengusaha-
pengusaha besar, terutama melalui hak pengusahaan hutan (HPH). Demikian pula tumbuhnya
konglomerat secara kasat mata menunjukkan pemilikan pribadi yang tidak terbatas (Rochadi,
2018). Kompetisi antar pelaku bisnis dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi, sehingga bukan
hanya harga yang setara dengan barang yang dibeli, tetapi juga kualitas. Persaingan terjadi bukan
27
hanya di kalangan produsen tetapi juga para pekerja. Mereka ini berusaha merebut lapangan kerja
dan meningkatkan karir untuk menduduki jabatan-jabatan penting baik di perusahaan maupun di
pemerintahan. Hanya kualitas yang membuat mereka mampu meniti karir dan bertahan. Penerapan
rasionalitas dalam perekonomian kapitalis terutama diterapkan dalam pengambilan keputusan.
Hanya alternative yang paling besar memberi keuntungan, membuat perusahaan mampu bertahan
dan memenangkan persaingan, yang paling mungkin dipilih.
Baumol, Litan dan Schramm ( 2010) mendefinisikan kapitalisme secara sederhana, hanya
mencakup satu unsur dari tiga unsur di atas. Menurut mereka suatu perekonomian dikatakan
bersifat kapitalistik ketika sebagian besar atau sejumlah porsi yang signifikan dari alat-alat produksi
yang ada di dalamnya (lahan pertanian, pabrik-pabrik, mesin-mesin) dimiliki oleh sector swasta.
Arbercombrie (dalam Rahardjo, 1989) menyebutkan sejumlah ciri kapitalisme dalam bentuknya
yang murni, yaitu (1). pemilikan dan control atas sejumlah instrument produksi , khususnya capital
dilakukan oleh swasta, (2). Pengarahan kegiatan ekonomi kea rah pembentukan laba; (3). Adanya
kerangka pasar yang mengatur semua kegiatan, (4). Apropriasi laba oleh pemilik modal, dan (5).
Penyediaan tenaga kerja oleh buruh yang bertindak sebagai agen bebas.
Surplus pertanian dan kemudian Revolusi Industri, merupakan faktor penting
pembentukan kapitalisme. Adanya surplus pertanian telah memungkinkan lahirnya golongan yang
menikmati kekayaan tanpa bekerja. Mereka ini antara lain tuan-tuan tanah dan pedagang. Laba dan
kekayaan mereka selanjutnya diinvestasikan di sector off-farm yang menjadi embrio industrialisasi.
Secara historis, Meghnad Dessi (dalam Rahardjo, 1989) mengemukakan ciri-ciri kapitalisme
berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu (1). Produksi untuk dijual dan bukan untuk
dikonsumsi sendiri; (2). Adanya pasar, di mana tenaga kerja djual dan dibeli melalui alat tukar upah
dan hubungan industrial; (3). Penggunaan uang sebagai alat tukar yang selanjutnya memberi
peranan yang sistematis kepada bank dan lembaga keuangan non bank; (4). Proses produksi dan
proses kerja berada dalam kontrol pemilik modal dan agen-agen managerialnya; (5) kontrol dan
keputusan keuangan berada di tangan pemilik modal dan para pekerja tidak ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan itu; (6). Berlakunya persaingan bebas di antara pemilik capital.
Ciri-ciri kapitalisme yang dikemukakan oleh Arbercombrie dan Meghnad Dessi di atas
merupakan kapitalisme murni yang dikecam oleh para humanis. Model kapitalisme seperti itu
menginjak-injak keadilan, terutama dengan mengeksploitasi buruh, menyedot tenaga kerja buruh
untuk keuntungan para kapitalis. Kapitalisme model klasik semacam itu pernah hidup di Inggris
28
dan Amerika Serikat pada abad XIX dan sering dikenal sebagai jaman laissez faire. Rejim laissez
faire, persaingan bebas dan sering kali disebut sebagai ekonomi klasik dicirikan oleh tumbuh dan
berkembangnya usaha-usaha kecil dan menengah yang dimiliki perorangan dan keluarga yang
menjalankan usaha secara bebas. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam masyarakat berlangsung di
bawah pengaturan sistem pasar. Dalam sistem ini alokasi buruh atau tenaga kerja di antara para
majikan melalui sistem upah dan kontrak kerja dalam pasar tenaga kerja. Negara tidak melakukan
intervensi dalam sistem pasar dan membiarkannya berkembang secara bebas.
Sistem kapitalisme klasik semacam itu telah menyapu ribuan industri kecil dan
mengokohkan pemilik modal kuat. Hubungan industrial yang terbangun adalah hubungan
eksploitatif, di mana para buruh semata-mata dilihat dari tenaga kerjanya. Buruh dibayar dengan
konsep “no work, no pay”. Besarnya upah ditentukan oleh produktivitasnya. Oleh karena langkanya
pekerjaan, maka berlangsung kompetisi antar pekerja untuk mendapatkannya. Kondisi ini
menguntungkan pengusaha, di mana pengusaha bisa membayar upah buruh murah. Kebutuhan
untuk mempertahankan hidup, membuat buruh tidak punya pilihan. Pada pasar tenaga kerja yang
tidak seimbang, terutama dalam situasi tenaga kerja yang oversupply, hubungan industrial berjalan
searah di mana pengusaha memaksakan kehendaknya. Pengusaha menentukan jam kerja, upah,
memberikan alat-alat kerja yang terbatas dan menuntut diselesaikannya pekerjaan dalam jumlah
tertentu. Pekerja dalam posisi lemah. Perlindungan bagi mereka sangat minim yang berakibat
mudahnya pekerja kehilangan pekerjaan.
Dorongan akumulasi kapital adalah pencarian laba sebesar-besarnya dan hal ini memberi
alasan bagi kapitalis untuk melakukan eksploitasi kepada pekerja. Dalam hubungan industrial di
mana satu pihak menguasai modal dan menjadi penentu nasib pekerja, maka tidak mungkin
terbangun hubungan setara. Hubungan industrial yang dicirikan oleh ketimpangan sumberdaya
membawa kepada hubungan dominasi. Dalam teori politik, dominasi satu kelompok atas yang lain
dilengkapi dengan wewenang, hak untuk memutus hubungan, dan mementukan kondisi sosial
ekonomi kelompok yang didominasi. Pekerja berusaha mengimbangi dengan membangunserikat
atau organisasi. Organisasi menjadi alat untuk menghadapi wewenang pengusaha yang sangat luas.
Tetapi berbeda dengan pengusaha yang hanya terdiri beberapa orang, bahkan sering hanya satu
orang; pekerja jumlahnya banyak dan sangat sulit menyatukan pendapat serta sikap politik. Apalagi
sebagian pekerja bersikap pragmatis dengan menolak bergabung dalam serikat karena takut
29
kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, jumlah pekerja yang banyak belum tentu memiliki
kemampuan tawar menawar yang kuat.
Sistem kapitalisme dapat bekerja dengan baik jika persaingan bebas berjalan. Persaingan
tersebut bukan hanya antar pengusaha tetapi juga antar pekerja. Ideologi pasar bebas tidak
mengenal hak asasi manusia, nasionalisme dan keadilan. Sebaliknya ideologi ini sejalan dengan
liberalisme yang menuntut kebebasan individu, akumulasi modal dan pemupukan kekayaan. Dalam
hubungan kerja, ideologi semacam ini mewujud dengan mendorong pekerja bekerja seoptimal
mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Dalam bidang ekonomi, Adam
Smith dengan tesisnya “pasar yang terbebas dari intervensi pemerintah akan menghasilkan
kemakmuran maksimum bagi seluruh bangsa” dikenal sebagai peletak dasar kapitalisme dan
liberalisme.
Dalam perjalanannya, kapitalisme telah mengalami banyak koreksi, termasuk
memasukkan unsur-unsur sosialisme, sehingga Samuelson ahli ekonomi klasik itu menyatakan
tidak ada lagi Negara dengan sistem ekonomi kapitalisme murni dan sosialisme murni, yang ada
adalah sistem ekonomi campuran. Kapitalisme itu sendiri tidak tunggal. Di Indonesia dikenal
kapitalisme negara (Robinson, 1986) dan kapitalisme semua (Kunio, 1992). Baumol, Litan dan
Schramm ( 2010) yang mempelajari kapitalisme abad XXI menyatakan ada empat varian
kapitalisme, yaitu kapitalisme arahan Negara, kapitalisme oligarki, kapitalisme perusahaan besar
dan kapitalisme kewirausahaan.
Dalam kapitalisme arahan Negara, pemerintah berusaha mengarahkan pasar dengan
mendukung industri tertentu yang diharapkan menjadi pemenang. Di Indonesia khususnya selama
masa Orde Baru, pemerintah berperan aktif dalam pembangunan. Pemerintah berusaha
mengarahkan jenis-jenis industri yang bias berdiri dan berkembang. Untuk mendukungnya,
pemerintah juga mengendalikan buruh melalui strategi state corporatism. Dalam strategi ini setiap
bidang kehidupan atau bidang-bidang fungsional, hanya diijinkan satu organisasi. Organisasi ini
disponsori pemerintah, diberi dana, pemimpin-pemimpinnya harus mendapat restu pemerintah dan
setelah duduk sebagai pemimpin, harus mengarahkan dukungan penuh kepada pemerintah.
Misalnya, untuk petani hanya ada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), untuk buruh
hanya diijinkan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian menjadi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI). Hubungan industrial yang secara resmi mengikuti konsep Hubungan
Industrial Pancasila (HIP), dalam prakteknya buruh mendapat intimidasi dan eksploitasi oleh
30
aparatur pemerintah, khususnya militer. Dalam situasi semacam itu, HIP hanya menjadi jargon dan
alat bagi kekuasaan untuk menekan buruh.
Jika dalam kapitalisme arahan Negara kebijakan-kebijakan pemerintah sebagian besar
dirancang untuk memenuhi kepentingan segelintir masyarakat (biasanya kepentingan para penguasa
beserta keluarga mereka), maka kapitalisme arahan Negara berubah menjadi kapitalisme oligarki.
Kapitalisme perusahaan besar, di mana aktivitas-aktivitas ekonomi yang paling penting dijalankan
oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan. Inilah yang lazim disebut kapitalis yang
sering sulit dibedakan dengan industrialis. Watak otoriter rejim terhadap buruh semakin kentara
dalam kapitalisme oligarki karena Negara dan pejabatnya menggunakan kebijakan dan kemudian
kekayaan Negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di era dasawarsa terakhir Orde Baru,
watak kapitalisme oligarki sangat menonjol. Berbagai proyek strategis dan proyek-proyek lain
dikuasai oleh keluarga-keluarga pejabat Negara. Proyek jalan tol dikuasai oleh putri pertama
presiden Soeharto, proyek mobil nasional dikuasai oleh putra bungsu Presiden Soeharto, demikian
pula proyek-proyek lain yang terbagi kepada anak-anak pejabat Negara.
Dalam ekonomi politik seperti itu, hubungan industrial tidak mungkin berpihak kepada
pekerja. Buruh diposisikan sebagai orang-orang yang telah memperoleh belas kasihan pemilik
modal dan karenanya tidak layak melancarkan demonstrasi, mogok dan menuntut hak-hak lainnya.
Jika para buruh tidak puas dengan kondisi kerja yang ada, maka diberi kebebasan untuk
mengundurkan diri. Sistem kapitalisme perusahaan besar juga tidak kalah eksploitatif karena
perusahaan-perusahaan ini menjadi besar atas jasa aparatur Negara. Oleh karena itu para kapitalis
harus membalas jasa baik aparatur Negara, baik dengan menempatkan salah satu petinggi militer
dalam jajaran komisaris maupun memberikan “upeti”. Uang untuk upeti yang sesungguhnya
diperoleh dari laba (pada hal pengusaha tidak mau kehilangan laba), maka dibebankan kepada
buruh. Dalam format semacam ini, upah buruh tidak naik meskipun perusahaan memperoleh
keuntungan besar. Anggaran untuk menaikkan upah buruh diberikan kepada pejabat Negara yang
telah berjasa membangun ketenangan bisnis dan menciptakan etertiban.
Kapitalisme kewirausahaan di mana perusahaan-perusahaan kecil yang inovatif
memainkan peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Kunci keberhasilan kapitalisme
kewirausahaan adalah inovasi yang terus menerus dan kadang-kadang radikal. Berbagai hasil
inovasi tersebut telah meningkatkan standar hidup masyarakat, jauh melampaui era sebelumnya.
Misalnya, pesawat terbang, telepon yang kemudian berkembang menjadi teknologi yang sangat
31
canggih yang mampu menghubungkan orang per orang. Seperti dikemukakan oleh Audrestch
(dalam Baumol, Litan dan Schramm (2010), kewirausahaan memberi konstribusi penting pada
pertumbuhan ekonomi, dengan menyediakan saluran untuk menyebarkan pengetahuan yang
sebelumnya tidak dapat dikomersialisasikan. Oleh karena kompetisi antar perusahaan swasta bukan
hanya memerlukan efisiensi tetapi juga inovasi, maka hubungan industrial yang terbangun lebih
manusiawi dibanding pada jenis kapitalisme sebelumnya. Perlunya memperlakukan pekerja lebih
manusiawi didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan gagasan-gagasan segar dari pekerja guna
memenangkan kompetisi. Dengan demikian, hubungan industrial dalam sistem kapitalisme
bermacam-macam tergantung pada watak dominasi dan kebutuhan pemilik modal terhadap jasa
tenaga kerja.
2.2.2. Teori Hubungan Industrial dalam Perspektif Sosialis
Sosialisme sebagai sebuah cita-cita politik dibentuk oleh perlawanannya terhadap
kapitalisme. Pandangan dasarnya adalah umat manusia sebagai makhluk sosial yang ditentukan
oleh kemanusiaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia dibentuk oleh lingkungannya melalui
proses interaksi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dibanding bercita-cita sebagai individu
yang sukses mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pribadi melalui kompetisi, manusia lebih
bercita-cita memenuhi kebutuhan materialnya melalui kerjasama. Kesetaraan, kohesi sosial dan
kerjasama merupakan karakter utama sosialisme. Dalam waktu singkat khususnya di awal revolusi
industri yang ditandai dengan ketimpangan, kemiskinan absolut di kawasan Eropa dan
pengangguran yang tinggi, ideology sosialisme berkembang dengan cepat. Tumbuh dan
berkembangnya kelas pekerja mendorong gagasan sosialisme semakin luas dan menjadi penantang
utama kapitalisme.
Kaum buruh menjadi pendukung utama system ekonomi sosialis karena dalam system
ekonomi kapitalis, kaum buruh yang paling menderita. Mereka bekerja rata-rata 12 jam sehari,
menerima upah rendah, anak-anak dan kaum perempuan umumnya terlantar, kondisi kesehatan
yang buruk, kemiskinan dan pengangguran sangat mencolok. Selain itu, para pekerja generasi
pertama industrialisasi rata-rata mengalami disorientasi di mana mereka (sebagian besar)
sebelumnya sebagai petani dengan kekerabatan yang tinggi, kemudian menjadi bagian dari
masyarakat industri. Situasi di atas kemudian membawa para buruh pada ide-ide radikal, seperti
32
halnya gagasan Karl Marx. Eksploitasi terhadap kelas buruh membawa kaum proletariat ini tidak
punya pilihan lain kecuali harus melakukan revolusi untuk merebut dan menguasai kapital dan
menciptakan masyarakat tanpa kelas.
Sosialisme pada abad ke 19 telah mengalami perubahan besar. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat khususnya para pekerja bahkan mereka sudah bisa memiliki saham perusahaan melalui
pembelian perusahaan yang go public, buruh tidak tertarik melakukan revolusi. Dalam studi tentang
sosialisme, Heywood (2016) membedakan sosialisme revolusioner dan sosialisme evolusioner.
Yang pertama lebih berkiblat ke revolusi Rusia 1917 dengan Lenin dan kaum Bolsheviks sebagai
pelopornya, yang kedua merupakan sosialis reformis atau demokrasi sosial. Selain itu ada bentuk
sosialisme lain yaitu sosialisme di dunia keiga yang timbul sebagai reaksi terhadap kolonialisme
dan imperalisme. Ide eksploitasi kelas diganti dengan penindasan kaum kolonialis, sehingga
sosialisme melebur dengan nasionalisme untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Bentuk sosialisme
yang berbeda juga muncul di Arab dan Afrika yaitu dengan memadukan nilai-nilai tradisional
kesukuan dan prinsip-prinsip moral dalam agama Islam.
Sosialisme yang lebih umum merupakan prinsip dasar bagi gerakan buruh. Dalam
pandangan buruh, sosialisme sangat tepat sebagai cita-cita untuk membangun struktur masyarakat
yang lebih adil. Pada umumnya gagasan sosialisme bersumber pada Theimer yang dikenal sebagai
peletak dasar sosialisme purba (Magnis Suseno, 2000). Dikemukakan oleh Theimer, bahwa
pemilikan bersma akan menciptakan dunia lebih baik, membuat situasi ekonomi semua orang sama,
tidak ada ketimpangan kaya-miskin, dan menggantikan usaha mengejar kekayaan pribadi dengan
kesejahteraan umum. Gagasan sosialisme kuno tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran agama.
Penganjur sosialisme kuno, Thomas More (1478-1535) yang menulis buku Utopia, berkhayal
mengenai masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat sosialis. Utopia merupakan nama suatu
pulau yang dihuni oleh masyarakat yang merupakan khayalan More. Khayalan ini kemudian
menjadi cita-cita sosialisme, seperti semua orang harus bekerja dan menikmati pendapatan yang
sama, para pekerja bekerja di tanah atau usaha kecil milik sendiri bukan sebagai pemilik melainkan
sebagai pekerja komunitas, waktu bekerja sehari 6 jam. Gambaran Utopia ibarat surga, tidak ada
konflik dan yang ada hanya kesetaraan. Masyarakatnya damai, sejahtera dan hidup saling
bekerjasama.
33
Kondisi kelas pekerja yang buruk mendorong munculnya sosialisme modern. Berbeda
dengan Utopia-nya Thomas More yang ditulis sebelum kapitalisme berkembang, sosialisme
modern disusun setelah kapitalisme berkembang pesat. Artinya telah ada bukti-bukti bahwa
motivasi pencarian laba yang sebesar-besarnya dengan menindas hak-hak buruh, melahirkan
kemiskinan dan pengangguran. Pembagian laba yang adil ini yang mendasari gagasan kaum sosialis
modern. Bahwa buruh bekerja keras dan berhak menikmati hasil kerjanya, produk pekerjaan tidak
seharusnya menyingkirkan pekerja, justru harus merupakan milik pekerja. Pemikir lainnya, Saint
Simon (dalam Suseno, 2000) menambahkan bahwa kunci pembangunan masyarakat yang lebih adil
adalah perubahan bentuk hak milik. Hak milik tidak dihapus, namun dikaitkan dengan prestasi yang
bersangkutan dalam proses produksi. Simon hendak mempromosikan gagasan bahwa kesejahteraan
masyarakat berbanding lurus dengan kerja keras. Ia menolak revolusi dan perebutan alat-alat
produksi oleh karena menguntungkan mereka yang tidak pernah bekerja.
Robert Owen, seorang pemikir dan pekerja sosial asal Inggris pada awal abad XIX berusaha
meyakinkan para pengusaha untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil. Tatanan
industrial, keuangan, pengupahan dan pendidikan perlu direformasi (Suseno, 2000). Sebagai
seorang manajer pabrik, Owen melakukan perubahan besar seperti membangun perumahan bagi
buruh, membuka toko untuk belanja para buruh yang harganya lebih rendah dibanding toko lain,
dan membuka sekolah bagi anak-anak. Sekitar 30% buruh di Inggris kala itu berusia antara 6-14
tahun. Ternyata memberi dampak besar, semangat kerja dan hasil kerja buruh meningkat.
Peningkatan pendapatan bagi buruh juga menguntungkan perusahaan karena daya beli buruh
meingkat sehingga produk perusahaan lebih banyak terjual. Owen semakin yakin, bahwa reformasi
tatanan industrial harus segera dilakukan untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil.
Hubungan industrial dalam teori Owen harus berpihak kepada buruh secara nyata. Jika hak-
hak buruh terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dipenuhi, maka akan membangkitkan
gairah kerja dan produktivitas kerja. Para pengusaha memetik keuntungan lebih besar dibanding
melakukan pemangkasan hak-hak buruh. Peningkatan pendapatan buruh juga berdampak besar bagi
kesejahteraan masyarakat. Selain mendorong penjualan barang lebih besar karena konsumsi
meningkat, juga meningkatkan pemerataan. Gagasan Owen inilah yang kemudian berkembang
dalam teori pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan pangan, pakaian dan perumahan yang
terpenuhi membuat para pekerja lebih berkonsentrasi dalam proses produkti. Pekerja tidak perlu
34
takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan. Hubungan industrial tidak perlu eksploitatif, karena
bagaimana pun pengusaha tetap memerlukan buruh dalam produksi. Sebaliknya, dengan saling
menjalankan peran masing-masing secara normatif dan memenuhi kebutuhan pokok buruh, maka
manfaat yang lebih besar dapat diperoleh.
Di kalangan pemikir sosialis, sosialisme evolusioner dengan jalan parlementer yang lebih
berkembang. Jalan parlementer menuju masyarakat sosialis lebih realistis karena pemikiran
sosialisme perlu disemaikan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, pembentukan partai
sosialis yang pendukung utamanya bukan hanya kelas pekerja sangat penting. Partai sosialis perlu
memperluas basis sosial untuk memperoleh kekuasaan dan perubahan struktur politik melalui jalan
parlementer bisa dilakukan. Dengan demikian lebih baik melakukan perubahan gradual, bertahap
dengan membentuk pemikiran dan basis sosial yang kuat untuk menciptakan masyarakat sosialis,
dibanding melakukan revolusi sosial. Para penganjur sosialisme evolusioner seperti Beatrice Webb
(1858-1943) dan Sidney Webb (1859-1947) aktivis sosial asal Inggris, lebih menerima teori liberal
tentang peran negara sebagai yuri.
Optimisme para penganjur jalan parlementer menuju sosialisme didasari oleh beberapa
pertimbangan berikut (Heywood, 2016):
a. Meluasnya hak-hak politik di kalangan warga negara, terutama hak untuk memilih yang
pada akhirnya memunculkan kesetaraan politik.
b. Kesetaraan politik itu pada akhirnya akan memenangkan kelompok mayoritas dalam
industri yaitu kelas pekerja.
c. Sosialisme merupakan rumah alamiah kelas pekerja karena watak kapitalisme yang
eksploitatif. Semakin membesarnya kelas pekerja, semakin kuat pendukung partai sosialis,
sehingga kemenangan dan lahirnya masyarakat sosialis tinggal menunggu waktu.
d. Sekali saja partai sosialis memegang kekuasaan, maka transformasi sosial akan berjalan
terus. Demokrasi politik membuka kemungkinan meraih sosialisme secara damai.
Namun sosialisme demokratis ini menghadapi masalah yang belum dibayangkan oleh para
pemikir abad 19, yaitu masihkah kelas pekerja menjadi pemilih mayoritas di masyarakat industri
maju. Seiring berbagai perubahan yang dilakukan kapitalisme, seperti penjualan saham (go public),
bergesernya posisi pemilik dari kursi manajerial dan digantikan manager profesional, serta
35
munculnya dekomposisi kelas pekerja (Dahrendorf, 1986), ditemukannya pasar global,
berkembangnya multi national corporation (MNC) dan berlangsungnya globalisasi pasar tenaga
kerja; sosialisme tidak lagi menjadi inat kelas pekerja. Jatuhnya negara-negara komunis digantikan
oleh rejim lain yang lebih pro pasar, semakin menggemakan matinya sosialisme.
Gagasan hubungan industrial dalam perspektif sosialis tinggal cita-cita, seiring dengan semakin
besarnya perubahan atau penyesuaian kapitalisme yang semakin manusiawi. Runtuhnya Tembok
Berlin tahun 1989-1990, tidak menyisakan lawan kapitalisme di negara industri maju. Penulis
Amerika Serikat keturunan Jepang, Francis Fukuyama (2009) menyimpukan berakhirnya sejarah,
kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Dalam perspektif semacam itu, sosialisme tetap
diperlukan untuk mengubah watak kapitalisme agar semakin humanis. Seperti telah dikemukakan
di atas, dewasa ini tidak ada lagi negara yang mempraktekkan kapitalis murni dan sosialisme murni,
yang ada adalah perekonomian campuran. Kapitalisme semakin mendekatkan diri dengan
sosialisme, sehingga wajah aslinya semakin tidak jelas di akhir Abad XX.
Dalam sistem ekonomi sosialis, keadilan sangat mungkin dicapai karena alat-alat produksi
terutama industri besar dan strategis dimiliki Negara. Sedangkan industri kecil bisa dimiliki oleh
perorangan. Pengertian industri strategis tentu berubah sesuai dengan pekembangan ekonomi dan
politik suatu Negara. Industri kain di Indonesia tahun 1950-an termasuk strategis karena pakaian
dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Tahun 1970-an berubah ketika para investor asing
semakin banyak berinvestasi di bidang ini. Demikian pula industri kertas mulai beralih ke swasta
sejak tahun 1970-an. Jika dalam perekonomian kapitalis harga ditentukan oleh kekuatan permintaan
dan penawaran, demikian pula upah tenaga kerja; dalam perekonomian sosialis harga ditentukan
oleh pemerintah.
Dalam konsep sosialisme, hubungan industrial menampakkan wajah yang lebih pro kepentingan
buruh. Hal ini bisa terwujud dengan sejumlah prinsip dan elemen kelembagaan sebagai berikut:
1. Di setiap perusahaan terdapat serikat buruh yang mewakili kepentingan semua buruh.
Serikat buruh menjalankan fungsi perundingan dengan pimpinan perusahaan,
memperjuangkan perubahan-perubahan aturan perusahaan yang merugikan buruh baik upah,
jam kerja, lembur, status buruh, dan berusaha mengurangi kekuasaan manajemen dan
menaikkan kekuasaannya sendiri. Agar berfungsi sebagai alat sosial dan ekonomi, serikat
36
buruh harus menjadi alat kekuasaan yaitu sebagai kekuatan pemaksa agar lawan-lawannya
menyerah (Schneider, 1986).
2. Para buruh didorong untuk menjadi anggota serikat buruh. Upah buruh yang menjadi
anggota serikat biasanya lebih besar dibanding yang tidak menjadi anggota serikat buruh.
3. Para aktivis serikat buruh bermental militan karena berhadapan langsung dengan pemilik
modal yang memiliki kekuasaan besar, seperti finansial, jaringan dengan penguasa dan
birokrasi. Namun umumnya militansi dibentuk oleh ideologi dan tantangan kekuasaan.
4. Serikat buruh mengontrol tenaga kerja yang akan masuk maupun ke luar dalam suatu
pabrik. Manajemen tidak bisa merekrut calon tenaga kerja tanpa persetujuan serikat buruh,
demikian pula jika ingin memberhentikan pekerja.
5. Perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan merupakan kesepakatan antara serikat buruh
dan pimpinan perusahaan.
Serikat buruh yang kuat menakutkan para pengusaha, karena mengurangi keleluasaan
pengusaha dalam mengoperasikan modalnya. Karena itu pengusaha lebih memilih bekerjasama
dengan pemerintah. Seperti dikemukakan sebelumnya, pemerintah melalui aparaturnya akan
melakukan tekanan kepada buruh untuk mentaati peraturan perusahaan, sekalipun dengan
kekerasan. Dalam kondisi kebebasan berserikat terbatas, pilihan bekerjasama dengan pemeintah
sangat menguntungkan. Sebaliknya, di era kebebasan berserikat, kekangan tidak lagi efektif, para
pengusaha menghadapi tekanan dari buruh. Di sini diperlukan perundingan bersama secara damai
untuk membangun kesepakatan kerja bersama.
2.2.3. Hubungan Industrial Pancasila (HIP)
Dalam konteks makro, studi hubungan industrial mencakup kajian terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah di bidang industri dan keteganakerjaan. Kajian dimaksud bukan hanya
mencakup proses perumusan kebijakan, tetapi juga implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses
perumusan kebijakan mengkaji bagaimana ide, gagasan isi kebijakan dirumuskan. Kemudian
bagaimana ide seseorang atau sekelompok orang menjadi agenda kebijakan yang berarti menggeser
ranah isu dari kelompok-kelompok di luar pemerintahan masuk ke dalam pemerintah. Tahap
selanjutnya, bagaimana proses perumusan kebijakan dalam system politik berproses. Apakah ada
37
kesesuaian antara gagasan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Tahap terakhir tentang
bagaimana rumusan kebijakan yang resmi disepakati menjadi keputusan dan menjadi produk
hukum, apakah bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam perumusan kebijakan
industrial, stakeholders utama adalah Kementrian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Serikat-
serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Kebijakan nasional yang menjadi rujukan pelaksanaan hubungan industrial terus mengalami
perubahan, mulai undang-undang kerja No. 12 tahun 1948 sampai undang-undang Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003. Meskipun demikian, mengingat falsafah bangsa adalah Pancasila, maka
hubungan industrial baik pada tingkat makro maupun mikro didasarkan pada sila-sila Pancasila.
Secara konseptual Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku-pelaku
industrial baik di tingkat makro maupun mikro yang didasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Para
pelaku industrial secara sederhana adalah pengusaha (pemilik perusahaan, manajer) dan para
pekerja baik secara langsung maupun diwakili oleh serikat pekerja. Dalam ruang lingkup lebih luas,
melibatkan pemerintah khususnya kementrian Tenaga Kerja atau level yang lebih rendah oleh
Dinas Tenaga Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah serikat-
serikat pekerja.
Dalam menjalankan konsep HIP, semua pihak harus berpegang pada asas kekeluargaan dan
gotong royong serta asas musyawarah untuk mufakat. Asas kekeluargaan mengandung makna
bahwa para pelaku usaha dan pekerja baik di tingkat makro maupun mikro memandang dirinya
sebagai bagian dari keluarga yang harus memberi konstribusi terhadap tegaknya keluarga. Institusi
Negara, bisnis, serikat pekerja dipandang sebagai institusi keluarga dan masing-masing sebagai
anggota keluarga. Oleh karena itu, satu sama lain memiliki kewajiban untuk membantu anggota
keluarga. Konsep kekeluargaan pertama-tama dikemukakan oleh Baruck de Spinoza ( 1632-1677 )
seorang filsuf keturunan Yahudi dan Portugis yang terkenal dengan teori kesatuan Allah dan
manusia. Konsep ini di Indonesia diambil oleh Prof. Soepomo sebagai salah satu asas dalam
mendirikan Negara Indonesia. Menurut Soepomo “Negara adalah susunan masyarakat yang
integral, segala golongan, segala bagian, segala anggota berhubungan erat satu sama lain dan
merupakan persatuan masyarakat yang organis”. Selanjutnya “Negara tidak memihak kepada suatu
golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak memihak kepentingan seseorang sebagai
38
pusat, Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat
dipisah-pisahkan”. Konsep Soepomo ini selanjutnya dikenal sebagai paham integralistik yang
memayungi asas kekeluargaan.
Dalam teori Negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo, Negara Indonesia
dipandang sebagai suatu bangunan keluarga. Rakyat Indonesia yang ada di dalamnya juga
memandang satu sama lain sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Masing-masing
mempunyai tanggung jawab demi tegaknya keluarga, majunya keluarga dan kemakmuran keluarga.
Jika konsep ini diterapkan dalam organisasi baik perusahaan maupun serikat pekerja, maka prinisp-
prinsip yang sama juga berlaku. Dalam suatu perusahaan, pemilik, manajer dan buruh adalah suatu
keluarga, sehingga satu sama lain harus bekerjasama, saling membantu (atau bergotong royong)
demi kejayaan perusahaan. Dalam suatu keluarga, ayah bertindak sebagai kepala keluarga. Maka
konsep kekeluargaan dan gotong royong ini juga berkembang ke konsep patron-client.
Menurut Keith R. Legg (1983) tautan hubungan tuan-hamba pada umumnya berkenaan
dengan hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumberdaya
yang tidak sama, hubungan yang bersifat khusus (particularistic), hubungan bersifat pribadi dan
sedikit banyak mengandung kemesraan (affectivity), dan hubungan yang berdasarkan asas saling
menguntungkan dan saling memberi dan saling menerima. Di Indonesia hubungan patronase bukan
hanya terjadi di kalangan birokrasi seperti dikemukakan oleh Jackson (1988), tetapi juga terjadi di
kalangan petani sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian James C. Scott (1992). Sedangkan di
kalangan buruh terjadi khususnya dalam merekrut dan mempekerjakan buruh dari daerah yang
sama. Kartini Sjahrir (1998) mengungkapkan bahwa untuk alasan kepercayaan dan keamanan diri,
para mandor cenderung merekrut buruh untuk dipekerjakan di Jakarta dari desa asal si mandor.
Oleh karena mereka yang datang ke kota belum memiliki pengalaman dan sumberdaya yang
memadai, maka para buruh tersebut di menumpang di tempat mandor. Dalam interaksi sehari-hari
para mandor bukan hanya memberi tumpangan tempat tinggal, tetapi juga memberi arahan kerja.
Mekanisme ini memposisikan si mandor sebagai tuan dan si pekerja sebagai hamba.
Prinsip musyawarah untuk mufakat menafikan pemungutan suara. Pola voting dianggap
sebagai perpecahan dan tidak menunjukkan adanya dukungan semua pihak dalam pengambilan
keputusan. Dengan voting, selain terjadi pembelahan, juga pihak yang kalah merasa dipermalukan
dan sering kali membentuk kekuatan tandingan. Banyak kejadian kongres suatu organisasi yang
39
berakhir dengan perpecahan karena pihak yang kalah tidak bisa menerima keputusan dan merasa
dipermalukan. Dengan musyawarah, semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan, semua
gagasan dibicarakan bersama kelebihan dan kekurangannya, sehingga keputusan akhir merupakan
kehendak bersama, dukungan bersama dan untuk kemajuan bersama.
Secara konseptual musyawarah merupakan proses pembahasan suatu tema dalam suatu
pertemuan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan secara aktif untuk mencapai suatu
keputusan sebagai penyelesaian masalah bersama. Oleh Mohammad Koesnoe (1980) musyawarah
disebut sebagai corak demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi semacam ini telah berakar dalam masyarakat adat
Indonesia selama ratusan tahun. Cara ini dilakukan agar proses dan hasilnya diterima secara
bersama. Mengingat sejarahnya dan merupakan nilai luhur yang telah melembaga dalam
masyarakat Indonesia, maka pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru menjadikannya sebagai
salah satu asas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sidang-sidang kenegaraan pun
diusahakan menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Dalam pelaksanaannya, HIP mengandung makna kerjasama antara pekerja dengan
pengusaha dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
a. Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah partner dalam proses produksi,
maksudnya baik pekerja maupun pengusaha wajib saling bekerjasama dalam melakukan
produksi dan meningkatkan produksi (partner in product).
b. Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah partner dalam pemerataan
menikmati hasil perusahaan yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan dinikmati
secara bersama-sama antara pekerja dengan pengusaha secara layak dan serasi sesuai
prestasi kerja (partner in profit).
c. Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah partner dalam tanggung jawab,
yang mencakup tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada
bangsa dan negara, tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab
kepada pekerja dan keluarganya dan tanggung jawab kepada perusahaan di mana mereka
bekerja (partner in responsibel).
40
Berbeda dengan hubungan industrial dalam perspektif ekonomi kapitalis maupun sosialis, HIP
memiliki ciri-ciri khusus yang merupakan gabungan nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan
produktivitas kerja. Ciri-ciri khusus HIP sebagaimana dikemukakan dalam Pedoman Pelaksanaan
Hubungan Industrial Pancasila (Departemen Tenaga Kerja 1987) adalah:
1. Hubungan industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan hanya
bertujuan mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian kepada Tuhan-nya, kepada
manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Hubungan industrial Pancasila bukan hanya menganggap pekerja sekedar faktor produksi
saja, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu
perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi faktor produksi saja,
melainkan harus dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Hubungan industrial Pancasila melihat pekerja dan pengusaha tidak memiliki kepentingan
yang bertentangan, tetapi memiliki kepentingan yang sama yaitu memajukan perusahaan.
Dengan perusahaan yang maju akan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
pengusaha.
4. Dalam hubungan industrial Pancasila setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan
pengusaha harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dilaksanakan secara kekeluargaan. Karena itu setiap penggunaan penekanan dan aksi-aksi
sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (lock out), bertentangan dengan prinsip-
prinsip hubungan industrial Pancasila.
5. Dalam hubungan industrial Pancasila, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban
kedua belah pihak dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan atas dasar
perimbangan kekuatan (balance of power), tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Di
samping itu, hubungan industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil
perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dengan pengusaha,
harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing.
Kebijakan yang lahir pasca Orde Baru khususnya UU 13 BAB XI yang mengatur tentang
hubungan industrial menetapkan Pasal 102 (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial,
pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
41
ketenagakerjaan. (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. (3) Dalam melaksanakan hubungan
industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan,
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh
secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana: a. serikat pekerja/serikat buruh; b. organisasi
pengusaha; c. lembaga kerja sama bipartit; d. lembaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Seperti peraturan-peraturan sebelumnya, UU13 juga
tidak secara tegas menyebut HIP. Dalam kebijakan sebelumnya seperti UU 14 tahun 1969 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
di Perusahaan Swasta, tidak menyebutkan HIP alih-alih menjelaskannya. Konsep HIP dan prinsip-
prinsipnya dirujuk dari Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (Departemen Tenaga
Kerja 1987). Dengan demikian, HIP sejak kelahirannya tahun 1974 melalui seminar hubungan
industrial yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, belum pernah
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga implementasi tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Hal
ini menyulitkan implementasinya di lapangan tentang siapa pemilik program, siapa penanggung
jawab akhir dan bagaimana susunan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, jika konsep dan
implementasi HIP berjalan setengah hati, sudah ditemukan penyebab awalnya.
42
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
Studi tentang hubungan industrial sangat luas karena hubungan industrial mencakup
berbagai aspek hubungan antara buruh dengan pengusaha. Hubungan antara kedua belah pihak
dapat dilakukan untuk mendeskripsikan kerjasama, konflik, ketegangan atau dilihat dari salah satu
pihak. Perspektif dari buruh dapat merupakan studi gerakan, aliansi antar serikat buruh, aliansi
antar serikat buruh dengan kelompok kepentingan lain atau dengan partai politik. Dari perspektif
pengusaha dapat merupakan studi tentang pengupahan, keselamatan kerja, faslitas kerja, tunjangan
kesejahteraan maupun pengembangan kualitas tenaga kerja oleh pengusaha. Sedangkan dari
perspektif pemerintah dapat merupakan studi kebijakan ketenagakerjaan secara umum, kebijakan
pengupahan, kebijakan keselamatan dan keamanan kerja, kebijakan investasi, kebijakan industry,
kebijakan kebebasan berorganisasi maupun kebijakan yang mengatur relasi buruh dengan
pengusaha.
Studi ini bergerak dari makro ke mikro, yaitu dari kebijakan tentang hubungan industrial ke
implementasinya di tingkat local. Isi kebijakan yang hendak didiskripsikan adalah peranan serikat
buruh, pengusaha dan pemerintah dalam membangun hubungan industrial khususnya HIP. Dalam
memenuhi maksud tersebut, dideskripsikan peranan masing-masing dan dicari ketidakterhubungan
(mismatch) antara pelaku. Lazimnya mismatch terjadi karena tuntutan masing-masing pihak tidak
terpenuhi, baik karena menyimpang dari aturan yang berlaku maupun salah satu pihak tidak
memiliki kemampuan untuk memenuhinya.
Secara umum tujuan studi ini hendak membangun data dan melakukan analisis data tentang
hubungan industrial di kawasan industri Karawang Timur. Dengan dimilikinya data dana
dilakukannya analisis data, penelitian ini secara konkrit membantu Universitas Nasional mencapai
rencana dan strategi penelitian melalui temuan-temuan konseptual dan metodologi bidang ilmu
sosial khususnya sosiologi. Dengan mengkaji hubungan industrial di Karawang yang merupakan
wilayah industri penelitian ini bertujuan menghasilkan invensi berupa konsep, teori dan kebijakan
baru bidang hubungan industrial. Selain itu tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data dan
43
melakukan analisis data yang akurat, kontemporer tentang hubungan industrial yang nantinya dapat
dipblikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Sedangkan secara khusus tujuan studi ini
adalah:
a. Tersedianya data dan analisis tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam perlindungan pekerja agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak?
b. Tersedianya data dan analisis tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam penentuan upah minimum kabupaten dan pelaksanaannya dalam konteks HIP?
c. Tersedianya data dan analisis tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) dan pelaksanaannya dalam konteks
Hubungan Industrial Pancasila?
d. Tersedianya data dan analisis tentang dipilihnya Peraturan Perusahaan oleh perusahaan-
perusahaan disbanding pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di kawasan
industri Karawang Timur ?
e. Tersedianya data dan analisis tentang pemagangan dan strategi pemerintah dalam
mewujudkan kepastian kerja bagi pekerja di kawasan industri Karawang Timur?
3.2. Manfaat Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka bagi institusi (Universitas Nasional) manfaat
yang diperoleh adalah pemenuhan (terpenuhinya) rencana strategis bidang penelitian. Sedangkan
bagi pengembangan sosiologi, manfaat yang diperoleh adalah diperolehnya data, analisis data yang
up-to date tentang hubungan industrial yang menjadi salah satu focus studi sosiologi di Universitas
Nasional. Selain itu mampu menaikkan prestise Prodi Sosiologi di kancah nasional dan
internasional melalui publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Manfaat lainnya adalah
diperolehnya konsep-konsep dan teori hubungan industrial yang up-to date, sebagai temuan
(invensi) baru bidang studi sosiologi.
44
Secara khusus manfaat yang diperoleh dari studi ini adalah:
1. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan
pemerintah dalam perlindungan pekerja untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja
sepihak.
2. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan
pemerintah dalam penentuan upah minimum kabupaten dan pelaksanaannya dalam
konteks HIP.
3. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan
pemerintah dalam penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) dan pelaksanaannya
dalam konteks Hubungan Industrial Pancasila.
4. Diperolehnya data dan informasi tentang dipilihnya Peraturan Perusahaan oleh
perusahaan-perusahaan disbanding pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di
kawasan industri Karawang Timur.
5. Diperolehnya data dan informasi tentang pemagangan dan strategi pemerintah dalam
mewujudkan kepastian kerja bagi pekerja di kawasan industri Karawang Timur.
45
BAB IV
METODE PENELITIAN
4. 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau yang populer disebut penelitian
alamiah (naturalistic). Neuman (2014) menyebutnya penelitian lapangan untuk membedakan
dengan pendekatan kuantitatif yang lazim dilakukan di laboratorium. Pendekatan kualitatif pertama
kali diperkenalkan oleh para antropolog, seperti yang yang dilakukan oleh Malinowski (1844-1942)
di Papua New Guinea (Papua Nugini sekarang) tahun 1914. Hasil penelitiannya kemudian dikenal
luas dan sumbangan metodologinya diakui oleh komunitas intelektual dunia sebagai metodologi
baru dalam ilmu sosial. Malinowski percaya bahwa cara terbaik untuk mengembangkan
pemahaman yang mendalam tentang suatu komunitas atau budaya adalah peneliti secara langsung
berinteraksi dan hidup di antara penduduk pribumi, mempelajari adat-istiadat, keyakinan dan proses
sosial mereka (Neuman, 2014).
Pendekatan kualitatif merupakan pilihan dalam studi ini karena peneliti ingin mempelajari,
memahami atau menggambarkan sekelompok orang yang berinteraksi, khususnya buruh,
pengusaha dan pemerintah (pejabat pemerintah yang berwenang di bidang perburuhan) di wilayah
Karawang. Seperti yang dilakukan oleh sosiolog dari Universitas Chicago yang kemudian dikenal
sebagai Chicago School, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipan. Peneliti
mempelajari buruh, serikat buruh, pengusaha dan para pejabat di bidang ketenagakerjaan dengan
mendatangi mereka, berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan
wawasan teoritis yang luas dari observasi dan wawancara.
Penelitian ini bertumpu pada prinsip naturalisme yang menuntut peneliti untuk
mengumpulkan informasi, menyusun informasi dan menjelaskan maknanya dalam latar sosial alami
dan berkesinambungan atas fokus pengamatan. Kehidupan sosial yang berkesinambungan
mengandung berbagai perspektif yang digunakan orang dalam latar sosial alami. Peneliti harus
menyatu dengan fokus penelitian atau lazim disebut objek penelitian untuk dapat menangkap secara
utuh fenomena yang dipelajari. Meskipun demikian, dibanding dengan penelitian etnografi dan
etnometodologi, penelitian ini berbeda. Pada kedua penelitian itu, pengetahuan budaya baik
46
eksplisit maupun tacit menjadi latar sosial budaya. Semua peristiwa dijelaskan dengan mengacu
kepada latar sosial budaya mulai dari pemikiran sampai tindakan. Pada penelitian ini oleh karena
ketiga pelaku yaitu aktivis serikat buruh, pengusaha dan pejabat bidang ketenagakerjaan tidak
tinggal di wilayah yang sama dan mereka tidak berinteraksi dalam budaya yang sama, maka latar
sosial budaya tidak menjadi dasar dalam analisis data.
Dengan kata lain, dibanding mengikuti salah satu perspektif dalam pendekatan kualitatif
misalnya perspektif etnografi atau etnometodologi, penelitian ini lebih mengikuti logika penelitian
kualitatif secara umum sebagaimana disarankan oleh Neuman (2014). Dengan mendeskripsikan
peristiwa dalam realitas otentik, menuntut peneliti masuk ke lokasi penelitian, berinteraksi dengan
para informan dan para partisipan. Prinsip lain adalah bahwa kehidupan sosial berkesinambungan
dengan berbagai perspektif. Untuk itu dalam memahami kehidupan sosial, peneliti harus
menggunakan berbagai perspektif khususnya dari para partisipan. Konsep partisipan mengacu pada
Creswell (2015) untuk menyebut semua pihak yang terlibat dalam penelitian khususnya mereka
yang menjadi informan.
4.2. Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan mengikuti saran dari Creswell (2015) yang
mencakup lima langkah (dalam penelitian ini diterapkan 3 langkah) disesuaikan dengan situasi
khusus yaitu Karawang sebagai wilayah industri. Pertama, mengidentifikasi partisipan dan tempat
yang akan diteliti serta terlibat dalam strategi sampling. Partisipan yang dilibatkan adalah pejabat
Dinas Tenaga Kerja khususnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Satuan Tenaga Kerja dinas
Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat, aktivis serikat buruh dari Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan Kesatuan Aksi Solidaritas
Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Singaperbangsa. Selain itu dilibatkan para pengusaha
yaitu Perwakilan perusahaan dan Penanggung Jawab SDM di Perusahaan dan Pengurus Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO). Pemilihan mereka mengikuti saran Patton (2002) yaitu memilih
partisipan dan lokasi penelitian yang kaya informasi. Selain itu ditambahkan saran Neuman (2014)
yaitu kekayaan data, ketidakakraban dan kesesuaian.
47
Kedua, mendapatkan akses ke individu dan tempat dengan mendapatkan ijin. Untuk bagian
ini peneliti telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Karawang, ketua SPSI Cabang
Karawang, Ketua PPMI Cabang Karawang, Ketua SP Singaperbangsa cabang Karawang, Ketua
KASBI Cabang Karawang, Perwakilan perusahaan dan Penanggung Jawab SDM di Perusahaan dan
Ketua APINDO Cabang Karawang dilampiri proposal. Semua pihak telah setuju dengan maksud
peneliti dan memberikan waktu wawancara minggu ketiga bulan Juli 2018, minggu ketiga bulan
Agustus 2018. Untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan buruh sehari-hari, para peneliti
tinggal di Karawang Timur selama 10 hari. Daerah Karawang Timur dikenal sebagai pemukiman
buruh di Karawang.
Gambar 4.2.1 Tangga akses yang dibangun oleh peneliti
Bagan diadaptasi dari Neuman (2014:473) dengan modifikasi peneliti
Peranan gate keeper sangat penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karena penelitian ini tentang
peranan serikat pekerja dalam mebangun hubungan industrial yang harmonis berdasarkan HIP,
maka gate keeper yang ditetapkan adalah ketua SPSI Cabang Karawang dan Ketua SP
Singaperbangsa. Dipilihnya mereka dengan pertimbangan dialah yang memberi pintu masuk,
memiliki akses yang baik ke APINDO, para buruh dan pejabat bidang ketenagakerjaan di
Karawang.
Mg 1, 2 Juni 18 Mg 3, 4 Juni 18 Mg 1,2 Juli 18 Mg 3, 4 Juli 18 AGT 18
48
Ketiga, mengidentifikasi tipe informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
Peneliti telah mengidentifikasi tipe-tipe data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian maupun
teknik mengumpulkannya. Sejak awal peneliti memahami bahwa data yang harus dikumpulkan
tidak mungkin diperoleh dengan teknik pengumpulan tunggal seperti wawancara. Di sini dilakukan
pengumpulan data secara terperinci, sistematis, lengkap yang diharapkan mampu menjawab
pertanyaan penelitian dan memberikan kebaruan (novelty) penting dalam studi hubungan
industrial. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Tipe Data
Teknik Pengumpulan Data Tipe Data Aktivitas Lapangan
Observasi Catatan Lapangan
dan foto
Peneliti melakukan observasi di
kawasan yang dihuni buruh, di
perusahaan daerah Citra Indah
Karawang Timur, sekretariat SPSI,
PPMI, KASBI, SPS, APPINDO.
Wawancara Pertanyaan terbuka Peneliti melakukan wawancara terhadap
partisipan yang terpilih yaitu para
pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Karawang, Direktur dan perwakilan
Perusahaan, Para Ketua Serikat
Pekerja/Buruh SPSI, PPMI, KASBI,
SPS, Ketua APINDO Karawang, Para
buruh di pemukiman. Wawancara
direkam kemudian ditranskripsi.
Dokumen Dokumen tertulis, Memeriksa informasi dan data dari
buku, majalah, notulen rapat, berita
surat kabar, web, dokumen yang dibuat
kantor pemerintah, Dok APINDO, Dok
SP/SB. Catatan harian peneliti.
Bahan audiovisual Foto dan rekaman Melakukan pemotretan, perekaman
aktivitas buruh di perusahaan, aktivitas
pejabat, pimpinan perusahaan maupun
para aktivis buruh
49
4.3. Uji Keabsahan Hasil Penelitian
Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai keabsahan hasil penelitian.
Banyak penelitian kualitatif diragukan karena masalah keabsahan data, seperti dominannya
subjektivitas peneliti dan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.
Untuk itu dilakukan pengujian keabsahan data yang oleh Denzin (2012) disebut triangulasi dan oleh
Burgess (dalam Bungin, 2014) disebut strategi penelitian ganda dan sering kali dengan sebutan
meta metode. Maksudnya penelitian yang menggunakan beberapa metode sekaligus dalam suatu
penelitian yang dilakukan secara linear atau silang untuk menguji keabsahan data atau kebenaran
data.
Pada penelitian ini dilakukan triangulasi. Oleh Denzin (2012) dikemukakan ada 4 (empat)
macam triangulasi, yaitu triangulasi kejujuran peneliti, triangulasi sumber data, triangulasi metode
dan triangulasi teori. Peneliti memilih triangulasi sumber data mengingat karakteristik partisipan
yang diteliti memiliki kepentingan berbeda tajam. Buruh bertujuan mendapatkan upah besar, jam
kerja terbatas fasilitas kerja lengkap dan status sebagai pekerja yang pasti, sedangkan pengusaha
memiliki kepentingan yang cenderung bertolak belakang. Dengan kepentingan semacam itu, sangat
mungkin informasi dari buruh dan pengusaha berbeda tajam. Untuk mencegah dan meminimalkan
penyimpangan, maka dilakukan uji keabsahan sumber data.
Gambar 4.3.1 Bagan Uji Keabsahan Data
Informasi dari
Pejabat Disnaker
Informasi dari SP/
SB, Buruh
Informasi dari
Pengusaha, APINDO
50
Selain mengikuti teori Denzin, uji keabsahan juga mengikuti teori Patton (2002) yang
dilakukan dengan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan partisipan di depan orang banyak dengan yang
dikatakan secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan partisipan seketika dengan apa yang dikatakan
sepanjang peneliti ada di lokasi penelitian
d. Membandingkan keadaan dan perspektif partisipan dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang lain seperti buruh biasa, dan pejabat pemerintahan
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen baik yang dimiliki SP/SB,
Disnaker dan Perusahaan.
4.4. Analisis Data
Strategi analisis data yang digunakan adalah gabungan tipe ideal dan hampiran berturutan
(successive approximation) yang dikemukakan oleh Neuman (2014). Konsep tipe ideal
dikemukakan oleh Max Weber untuk menunjukkan organisasi, kondisi, situasi, keputusan, interaksi
dan tindakan yang dinilai sempurna oleh peneliti. Tipe ideal tidak pernah ada dalam kenyataan,
melainkan hanya perangkat buatan. Seperti sistem politik demokrasi yang secara klasik mencakup
13 kriteria seperti dikemukakan oleh Held. Sistem politik demikian sulit diwujudkan, tetapi Negara-
negara yang percaya terhadap sistem itu berjuang memenuhi kriteria tersebut. Teknik analisis data
dengan tipe ideal ini membandingkan gagasan atau konsep ideal dengan kenyataan di lapangan
(pelaksanaannya), peneliti fokus pada hal-hal umum dan mencari penyebab umum dari kasus
hubungan industrial di Kabupaten Karawang.
Tipe ideal yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan prinsip hubungan
industrial Pancasila (HIP). Seluruh data yang dikumpulkan dibandingkan dengan konsep dan
prinsip HIP kemudian dicari penyebabnya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu teknik ini
menyerupai analisis deskriptif-kualitatif yang merupakan model analisis tahap pertama
perkembangan metode kualitatif (Denzin dan Lincoln, 2012). Teknik analisis data deskriptif-
51
kualitatif masih merupakan kualitatif semu, belum sungguh-sungguh kualitatif karena masih
memberi makna data dari perspektif teori yang digunakan.
Selain itu, digunakan teknik analisis data hampiran berturutan yang merupakan proses
penyusunan iterasi berulang. Peneliti bergerak dari teori HIP, klasifikasi data lapangan dari aktivis
serikat buruh, pejabat Dinas Tenaga Kerja, pengusaha, pimpinan APINDO dan buruh-buruh.
Kemudian memilah data berdasarkan tema baik yang menurut konsep HIP maupun tema lepas yang
menjadi kekhasan studi ini dan temuan lebih luasdari penelitian ini. Menurut saran Neuman (2014),
“peneliti menyelidiki data, mengajukan pertanyaan terhadap bukti untuk melihat seberapa baik
konsep sesuai dengan buktinya dan mengungkapkan ciri-ciri data. Peneliti juga membuat konsep
baru dengan melakukan abstraksi dari bukti menyesuaikan konsep agar lebih sesuai dengan
buktinya”. Dengan demikian, penggunaan hampiran berturutan (successive approximation)
merupakan proses yang berulang kali bolak-balik antara data empiris, konsep, teori atau model
abstrak, menyesuaikan teori dan menyempurnakan pengumpulan data.
Gambar 4.4.1 Bagan Strategi Analisis Data Tipe Ideal dan Hampiran Berturutan (successive
approximation)
Konsep dan prinsip
HIP:
a. Partner in
product
b. Partner in
profit
c. Partner in
responsibility
d. Humanisme
e. Pengabdian
f. Keharmonisan
g. Musyawarah
h. Keseimbangan
Pengumpulan dan
Klasifikasi Data
Data Pengupahan
Data Produksi
Data status Pekerja
Data konflik industrial
Dan seterusnya
Analisis Induktif
Temuan Penelitian
52
BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Bab ini menjelaskan tentang apa saja hasil yang telah kami peroleh pada tahun 1 (pertama).
Hasil atau output pada penelitian ini merupakan landasan untuk menyempurnakan capaian
luaran yang terdiri dari beberapa komponen yang dijelaskan pada tabel 5.1 dibawah ini.
5.1 Tabel Capaian Luaran Penelitian Tahun Satu
5.1 Hasil dan Luaran Tahun Satu Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional
Dalam penelitian ini, kami telah berhasil mendaftarkan (accepted) makalah yang merupakan
hasil dari rangkaian penelitian Peran Serikat Pekerja Dalam Membina Hubungan Industrial
Pancasila Antara Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang
Timur ini dengan judul yang kami sesuaikan dengan rencana penelitian tahun kedua atau lanjutan.
Hal tersebut tergambar dari referensi dan rekam jejak penelitian sebagai awal mula dalam rangka
mengoptimalkan capaian luaran penelitian ini hingga dapat dipublikasikan melalui jurnal
Internasional.
No Komponen Thn ke Hasil Capaian
1. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional 1 Accepted/ publish
2. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional 1 Terdaftar
3. Buku Ajar ISBN 1 Draf
4. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 1 Skala 3
5. Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 1 Submitted
6. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Lokal 1 Terdaftar
7. Model 1 Draf
8. Bahan Ajar 1 Editing
9. Kebijakan 1 Draf
10. Metode 1 Produk
11. Keikutsertaan dalam Seminar Internasional 1 Draf
12. Keikutsertaan dalam Seminar Nasional 1 Sudah dilaksanakan
53
Adapun judul dari makalah yang diterima adalah “The Declining Pancasila Industrial Relations
and the Increasing Industrial Conflicts, Research Findings from Karawang, West Java.” Akan
dipresentasikan oleh tim yaitu : Dr. Sigit Rochadi, M.Si, Angga Sulaiman, S.IP, MAP, dan penulis
lainnya yang berkontribusi terhadap penulisan makalah ini hingga di accepted adalah Adilita
Pramanti, S.Sos, M.Si.
5.1.1 Foto diskusi Proses penulisan Paper Internasional
5.1.2 Bukti Submit Jurnal Internasional
5.2 Hasil dan Luaran Tahun Satu Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional
Hasil dari luaran ini adalah makalah yang telah diselesaikan pada jurnal internasional dan
sudah ditranslete dalam bahasa inggris.Dalam prosesnya kami menggunakan data yang telah kami
54
dapatkan dilapangan selama penelitian berlangsung, namun kedepan pada tahun kedua kami ingin
lebih fokus temuan-temuan lain yang lebih spesifik dalam penelitian khusus pada kajian Hubungan
Industrial Pancasila dan Meningkatnya Konflik Industrial, Temuan dari Karawang Jawa Barat.
Gambar 5 .2.1 Bukti online penerimaan makalah untuk pertemuan Ilmiah Nasional
5.3 Hasil dan Luaran Tahun Satu Buku Ajar
Pada luaran buku ajar kami telah menghasilkan buku ajar berupa draft dan pada bulan September
akan didaftarkan ISBN. Adapun judul buku ajar kami adalah : “Paradigma Baru Hubungan
Industrial di Indonesia”
Dengan pembabakan Bab dan Sub Bab nya sebagai berikut :
1.Ruang Lingkup Hubungan Industrial
1.1 Kepentingan Perusahaan
1.2 Kepentingan Buruh
1.3 Peranan Pemerintah
2.Bentuk Hubungan Industrial
2.1 Peraturan Perusahaan
2.2 Perjanjian Kerja Bersama
3.Perkembangan Pemikiran Hubungan Industrial
3.1 Liberalisme
3.2 Sosialisme
3.3 Hubungan Industrial dalam Islam
4.Paradigma BAru Hubungan Industrial
55
4.1 Hubungan Industrial Pancasila
4.2 Paradigma Baru Hubungan Industrial
5.4 Hasil dan Luaran Tahun Satu Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
Tahap Kesiapan Teknologi atau Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) adalah ukuran tingkat kesiapan
teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu
teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna. Tingkat Kesiapan
Teknologi merupakan suatu sistem pengukuran sistematik yang mendukung penilaian kematangan
atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau kesiapan antara jenis
teknologi yang berbeda. Dalam penelitian ini kami telah telah melakukan pembuktian konsep pada
tahapan TKT 3 dimana dalam pembuktian TKT 3 ilmu sosial penyertaan fungsi atau karakteristik
dari Buruh yang kami teliti telah dijelaskan secara mendetail pada tahap metode penelitian secara
analitis melalui teori dan konsep ilmu sosial.
56
BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Dalam penelitian ini kami akan melakukan rancangan tahapan selanjutnya yaitu tahun kedua, yang
mana telah kami mulai juga terlebih dahulu dengan mendaftarkan 3(tiga) prosposal kami dengan
data penelitian atau temuan hasil dari penelitian ini, yaitu pada Kongres dan Seminar Nasional ISI
(Ikatan Sosiologi Indonesia) pada tanggal 25-28 Oktober 2018.
6.1.1 Keikutsertaan dalam kongres dan Seminar Nasional Sosiologi
Kemudian langkah selanjutnya kami akan membuat model kebijakan dalam hubungan Industrial
Pancasila yang memuat juga strategi hubungan tiga arah sehingga memperkuat luaran pada
penelitian ini. Kemudian kami juga berencana pada tahun kedua untuk menyelesaikan editing bahan
ajar sehingga dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa dalam kuliah Gerakan
Sosial di Program Studi Sosiologi pada khususnya dan program studi lain dengan kajian hubungan
industrial pada umumnya. Terakhir kami akan menambah keikutsertaan dalam seminar dan diskusi
yang fokus pada kajian buruh dan hubungan industrial Pancasila sebagai bahan kajian untuk
membuat kebijakan (policy brief) dan menemukan metode baru dalam analisis dan kajiannya.
57
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah
dicapai oleh tim peneliti. Melalui analisis dalam berbagai konteks makro dan mikro, studi
hubungan industrial mencakup kajian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang industri
dan keteganakerjaan. Kajian dimaksud bukan hanya mencakup proses perumusan kebijakan, tetapi
juga implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses perumusan kebijakan mengkaji bagaimana ide,
gagasan isi kebijakan dirumuskan. Kemudian bagaimana ide seseorang atau sekelompok orang
menjadi agenda kebijakan yang berarti menggeser ranah isu dari kelompok-kelompok di luar
pemerintahan masuk ke dalam pemerintah. Tahap selanjutnya, bagaimana proses perumusan
kebijakan dalam system politik berproses. Apakah ada kesesuaian antara gagasan pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Tahap terakhir tentang bagaimana rumusan kebijakan yang
resmi disepakati menjadi keputusan dan menjadi produk hukum, apakah bentuknya undang-undang
atau peraturan pemerintah. Dalam perumusan kebijakan industrial, stakeholders utama adalah
Kementrian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Serikat-serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO). Adapun hasil yang didapat adalah :
1. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam perlindungan pekerja untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.
2. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam penentuan upah minimum kabupaten dan pelaksanaannya dalam konteks HIP.
3. Diperolehnya data dan informasi tentang peranan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah
dalam penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) dan pelaksanaannya dalam konteks Hubungan
Industrial Pancasila.
4. Diperolehnya data dan informasi tentang dipilihnya Peraturan Perusahaan oleh perusahaan-
perusahaan disbanding pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di kawasan industri
Karawang Timur.
5. Diperolehnya data dan informasi tentang pemagangan dan strategi pemerintah dalam
mewujudkan kepastian kerja bagi pekerja di kawasan industri Karawang Timur.
58
Kebijakan nasional yang menjadi rujukan pelaksanaan hubungan industrial terus mengalami
perubahan, mulai undang-undang kerja No. 12 tahun 1948 sampai undang-undang Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003. Meskipun demikian, mengingat falsafah bangsa adalah Pancasila, maka
hubungan industrial baik pada tingkat makro maupun mikro didasarkan pada sila-sila Pancasila.
Secara konseptual Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku-pelaku
industrial baik di tingkat makro maupun mikro yang didasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Para
pelaku industrial secara sederhana adalah pengusaha (pemilik perusahaan, manajer) dan para
pekerja baik secara langsung maupun diwakili oleh serikat pekerja. Dalam ruang lingkup lebih luas,
melibatkan pemerintah khususnya kementrian Tenaga Kerja atau level yang lebih rendah oleh
Dinas Tenaga Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah serikat-
serikat pekerja. Untuk dapat mengoptimalkan hasil penelitian ini maka kami berharap dapat
melakukan kaji tindak hubungan industrial Pancasila di tahun kedua.
59
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
1. Friedrich Schneider. 1986. Measuring The Size of The Shadow Economy. Buckingham: The
Univeristy of Buckginham.
2. L. Leyendecker. 1983. Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sosiologi. Jakarta:
Gramdedia.
3. Suseno, Franz Magnis. 2002. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan
Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
4. George Ritzer. 2014. Introduction to Sociology. SAGE Publications
5. Caporaso, James A dan David P Lenin. 2016. Teori-Teori Ekonomi Politik. Jakarta: Pustaka
Pelajar.
6. Mintz, Jeanne S. 2012. Muhammad, Marx dan Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. William J Baumol, Robert E. Litan dan Carl. J Schramm. 2010. Good Capitalism, Bad
Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. Jakarta: Gramedia.
8. Robinson, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Jakarta: Komunitas Bambu.
9. Kunio, Yoshihara. 1992. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
10. Heywood, Andrew. 2016. Ideologi Politik: Sebuah Pengantar. Penerjemah: Yudi Santoso.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
11. Thomas More. 1516. The Best of Commonwealth and The New Island.
12. Ralf Dahrendorf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masayarakat Industri: Sebuah Analisa
Kritik. Jakarta: Rajawali Press.
13. Francis Fukuyama. 1992. The End History of The Last Man. Jakarta: Penerbit Qalam.
14. R Legg, Keith. 1983. Tuan, Hamba, dan Politisi. Jakarta: Sinar Harapan.
15. D Jackson, Karl and Lucian W. Pye. 1988. Political Power and Communication in Indonesia.
University of California Press.
16. Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.
Jakarta: Penerbit LP3ES.
17. Neuman, W Lawrence. 2014. Social Research Methods Qualitative and Quantitative
Approaches. New York: Pearson.
18. Cresswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
19. Patton, Michael Quinn. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods. USA: SAGE
Publications Inc.
20. Bungin, Burhan. 2003. Analisis data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo.
21. Denzin, N.K dan Lincoln, Y.S. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
22. Borsuk, Richard and Nancy Chng. 2014. Liem Sioe Liong Salim Group: The Business Pilar of
Suharto’s Indonesia. Singapore: Institute of Southest Asian Studies Publishing.
60
JURNAL
Rochadi, Sigit. 2014. Kebijakan Industrial(isasi) dan Kontinyuitas Konflik Industrial Pasca
Krisis Ekonomi 1997/1998. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Kebudayaan. Vol. 27 No. 2.
TESIS
Noorhadi Rahardjo. 1989. Penggunaan Foto Udara Untuk Mengetahui Kualitas Lingkungan
Permukaan di Kota Madya Magelang Dalam Hubungan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi
Penghuni. Tesis S2. Pascasarjana. UGM. Yogyakarta.
61
DRAFT BUKU AJAR
PARADIGMA BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
TIM PENULIS:
Dr. AF. SIGIT ROCHADI, M.SI.
ANGGA SULAIMAN, S.IP., M.AP.
ADILITA PRAMANTI, S.SOS, M.Si
JAKARTA, 2018
62
DRAFT BUKU AJAR PARADIGMA BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
BAB I. RUANG LINGKUP HUBUNGAN INDUSTRIAL I.1 Kepentingan Perusahaan I.2 Kepentingan Buruh I.3 Peranan Pemerintah BAB II. BENTUK HUBUNGAN INDUSTRIAL II.1 Peraturan Perusahaan II.2 Perjanjian Kerja Bersama BAB III. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUBUNGAN INDUSTRIAL III.1 Liberalisme III.2 Sosialisme III.3 Hubungan Industrial Dalam Islam BAB IV. PARADIGMA BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL IV.1 Hubungan Industrial Pancasila IV.2 Paradigma Baru Hubungan Industrial
63
BAB I.
RUANG LINGKUP HUBUNGAN INDUSTRIAL
Uraian Materi:
Mengawali Bab ini penulis lebih dahulu menjelaskan konsep dasar dari hubungan industrial yang
mencakup definisi, tujuan dan prinsip – prinsip sebelum menjelaskan kepentingan para pihak.
Sehingga mahasiswa atau pembaca pada umumnya dapat mendudukan pemahaman yang sama atas
nilai kepentingan sebagaimana dimaksud. Selanjutnya dijelaskan juga berbagai kepentingan dari para
pihak dalam hubungan industrial, yakni kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja dan peranan
pemerintah.
Capaian Pembelajaran:
• Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar hubungan industrial yang
mencakup: definisi, tujuan dan prinsip – prinsip hubungan industrial;
• Mahasiswa diharapkan mampu memahami bebagai kepentingan didalam hubungan
industrial; dan
• Mahasiswa mampu menganalisis konflik kepentingan dalam hubungan industrial.
Menurut McMillan dalam Umar Hasan, hubungan industrial merupakan interaksi antara para majikan, para
pegawai, pemerintah dan asosiasi – asosiasi lewat mana mediasi dari interasi tersebut dilakukan.
Pemerintah memiliki keterlibatan langsung sebagai pemberi kerja kepada pegawai – pegawainya dan
memiliki keterlibatan tidak langsung sesuai peranannya untuk mengatur ekonomi dan hubungan antara
para majikan, para pegawai dan serikat – serikat pekerja (Umar Hasan, 2013: 4). Dalam literatur lain,
hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa
(pengusaha), pekerja/serikat pekerja, dan pemerintah. Dimana hubungan industrial bertujuan untuk
64
menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pihak-pihak terkait tersebut (Sumanto
2013: 11).
Sekurangnya dari definisi di atas, maka pemaknaan dari hubungan industrial merupakan sebuah interaksi
para pihak (pengusaha, pekerja dan pemerintah) dalam kerangka membangun harmoni yang pada
gilirannya dapat mengakomodasi kepentingan bersama. Pemaknaan tersebut sejalan dengan tujuan akhir
dari pengaturan hubungan industrial yakni dalam konteks peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak.
Untuk sampai kepada kesejahteraan, diperlukan peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu dan
produktifitas dapat tercapai manakala terjadi hubungan yang harmonis/ketenangan kerja dilingkungan
perusahaan (Suwarto, 2006: 14). Dimana dalam memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut, ada beberapa
azas yang perlu diperhatikan sebagai berikut (Sumanto 2014: 16 - 17):
1. Asas Partner in Production
Menurut asas ini, buruh dan pengusaha mempunya kepentingan yang sama untuk meningkatkan
kesejahteraan buruh mampu meningkatkan hasil usaha/produksi. Oleh karena itu masing-masing
pihak merupakan kawan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan meningkatkan hasil
produksi.
2. Asas Partner in Profit
Menurut asas ini, hasil yang dicapai perusahaan itu seharusnya bukan untuk dinikmati oleh
pengusaha saja, tetapi harus dinikmati oleh buruh yang turut serta dalam mencapai hasil produksi
tersebut sehingga peningkatan kesejahteraan social para pekerja di perusahaan sejalan dengan
peningkatan hasil produksi.
3. Asas Partner in Responsibility
65
Menurut asas ini, buruh dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dalam
meningkatkan hasil produksi. Rasa tanggung jawab kedua belah pihak ini akan mendorong
peningkatan hasil produksi.
Masih dalam rujukan yang sama, prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan
semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial
mengandung prinsip-prinsip berikut ini :
1. Pengusaha dan pekerja, demikian juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama
mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Oleh sebab itu,
terutama pengusaha dan pekerja harus sama-sama memberikan upaya yang maksimal melalui
pelaksanaan tugas sehari-hari untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan meningkatkan
keberhasilan perusahaan. Pekerja dan serikat pekerja harus membuang kesan bahwa perusahaan
hanya kepentingan pengusaha. Demikian juga pengusaha harus membuang sikap yang
memperlakukan pekerja hanya sebagai factor produksi.
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak pengusaha yang
mengembangkan perusahaan atau membuka usaha baru, semakin banyak pekerja yang
memperoleh penghasilan. Semakin banyak perusahaan yang meningkatkan produktivitas, semakin
banyak pekerja memperoleh peningkatan penghasilan. Dengan demikian, pendapatan nasional dan
kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi
yang berbeda dengan pembagian kerja atau pembagian tugas. Pengusaha sebagai pemimpin
mempunya fungsi menggerakan, membina dan mengawasi. Pekerja mempunya fungsi melakukan
pekerjaan operasional. Pengusaha bukan mengeksploitas pekerja. Setiap pekerja melakukan
pekerjaan dalam waktu tertentu dalam satu hari dengan cukup waktu istirahat setiap hari dan hari
istirahat setiap minggu atau setiap bulan. Setiap pekerja melakukan tugas sesuai dengan beban
kerja yang wajar bagi kemanusiaan. Pekerja tidak mengabdi kepada pengusaha akan tetapi pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pembagian kerja seperti itu merupakan ciri organisasi
modern.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Sebagai anggota keluarga
meraka harus saling mengasihi, saling memerhatikan kepentingan yang lain dan saling membantu.
Pengusaha perlu memahami cara piker dan kepentingan pekerja yang tergabung dalam serikat
66
pekerja. Pengusaha perlu memerhatikan kondisi dan kebutuhan pekerjaan dan sedapat mungkin
memenuhinya. Sebaliknya pekerja dan serikat pekerja perlu memahami keterbatasan pengusaha.
Apabila timbul permasalahan atau persoalan harus diselesaikan secara kekeluargaan, tidak secara
bermusuhan.
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan
ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
Untuk itu masing-masing unsur mitra social-pengusaha dan pekerja-harus menjaga diri untuk tidak
menjadi sumber masalah dan perselisihan. Seandainya terdapat perbedaan pendapat, perbedaan
persepsi dan perbedaan kepentingan, harus diselesaikan secara kekeluarga dan diupayakan tanpa
menganggu proses produksi. Setiap gangguan produksi akan merugikan pengusaha, masyarakat
dan pengusaha sendiri.
6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu
kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Pekerja (yang ingin memperoleh upah lebih
tinggi) harus siap meningkatkan produktivitas kerjanya. Bila seorang pekerja menerima upah lebih
tinggi dari nilai kontribusi yang diberikan ke perusahaan, maka terpaksa ada orang lain yang
menerima upah lebih rendah dari nilai kontribusinya atau perusahaan harus memberikan subsidi.
Bila perusahaan terus memberikan subsidi, perusahaan akan sulit berkembang atau terancam
bangkrut. Sebaliknya pengusaha harus secara adil, tranparan, dan proporsional memberikan hasil
peningkatan produktivitas yang dihasilkan kepada pekerja.
I.1 Kepentingan Perusahaan
Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam bagian ini adalah unsur pengusaha/ investor/ pemilik
sebagai penyedia modal dan pemilik otoritas tertinggi dalam perusahaan. Karnanya dalam bagian ini secara
spesifik mengidentifikasi kepentingan perusahaan yang dilihat sebagai upaya untuk melipatgandakan aset,
dalam pengertian mencari tingkat rendemen bisnis/ keuntungan melaui peningkatan deviden dari aktivitas
perusahaan.
67
Lumrah, bahkan menjadi suatu keharusan ketika seorang pengusaha memiliki ambisi untuk mensukseskan
perusahaannya karena kesuksesan perusahaan akan linier dengan benefit yang diterimanya. Bahkan
indikator utama dari kesuksesan pengusaha diukur dari sejauhmana keuntungan yang diperolehnya. Bukan
hanya masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia hari ini, memberikan label “Pengusaha Sukses”
tentunya dengan melihat jumlah aset yang dimiliki.
Namun pelabelan dimaksud tidak serta merta sebagai bentuk respect masyarakat terhadap pengusaha,
karena belakangan nilai dan etika bisnis menjadi sorotan dalam dinamika perusahaan. Seiring
perkembangan pengetahuan dan teknologi, masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam penilaiannya.
Tuntutan akan keadilan, persamaan, kesempatan menjadi sangat substansial dalam menyoal hubungan
inudtrial.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Simanjuntak berikut, Masyarakat tidak begitu saja menaruh
hormat bagi orang kaya. Masyarakat sudah semakin kritis mengenai bagaimana seseorang
mengakumulasikan kekayaannya. Pengusaha dalam waktu singkat dapat melipatgandalan kekayaannya
diatas penderitaan karyawannya pasti tidak mendapat apresiasi dari masyarakat. Dalam era globalisasi dan
persaingan ketat sekarang ini, pengusaha seperti itu tidak akan mendapat dukungan ikhlas dari karyawan,
menjadi tidak produktif, tidak mampu bersaing, dan akhirnya akan gagal. Sebab itu, pengusaha yang dapat
sukses hanyalah pengusaha yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keluarga mereka (Payaman
J. Simanjuntak, 2011: 4 – 5).
Lantas pertanyaannya kemudian, apa saja yang menjadi kepentingan pengusaha di dalam perusahaan?
Sumanto (2013: 11) merinci kepentingan pengusaha sebagai berikut:
1. Menjaga dan mengamankan asetnya;
2. Mengembangkan modal/asetnya supaya memberi nilai tambah tinggi;
3. Meningkatkan penghasilan;
4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
5. Memperoleh aktualisasi diri melalui kesuksesan usaha.
68
Dari kelima hal diatas, penulis memerasnya kedalam 3 kepentingan. Kepentingan pengusaha dalam
konteks hubungan industrial adalah: Pertama, Meningkatkan aset/ penghasilan. Sudah barang tentu setiap
perusahan yang berorientasi profit akan mengejar keuntungan materil karenanya dalam pemahaman
penulis meningkatkan aset menjadi kepentingan yang utama.
Kedua, aktualiasasi diri. Disamping motif ekonomi kepentingan pengusaha lainnya adalah aktualisasi diri,
bahkan dalam Teori Hierarki Kebutuhan Maslow aktualisasi diri menempati puncak piramida dan motif
ekonomi yang tergolong dalam kebutuhan fisiologis (Physiological Needs) berada dalam posisi tertendah.
Fenomena pegusaha terjun kedunia politik atau semisal membeli jersey dengan harga ratusan juta dalam
bursa lelang hingga, terlihat “nyentrik” dihadapan pekerja merupakan pintu masuk untuk memahami
aktualisasi diri seorang pengusaha.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Umumnya dialektika yang berkembang menyoal hubungan
pengusaha dan pekerja dalam konteks kesejahteraan selalu dihadap hadapkan. Untuk mendapatkan
keuntungan yang besar seorang pengusaha harus mampu menekan biaya produksi, salah satu caranya
dengan membayar pekerja dengan upah yang begitu murah. Kondisi ini setali tiga uang dengan praktek
kolonialisme yang bernilai eksploitatif dan jauh dari nilai – nilai kemanusiaan.
Cara tersebut jelas – jelas keliru jika dipilih pengusaha hari ini, karena pekerja semakin hari semakin cerdas.
Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih kepada para pekerja dengan memposisikan mereka sebagai
mitra sehingga, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan termasuk didalamnya aspek
kesejahteraan. Jika tercipta kondisi demikian maka bisa dipastikan produktifitas pekerja menjadi lebih baik
yang pada gilirannya mampu mendongkrak performa perusahaan secara keseluruhan.
69
I.2 Kepentingan Buruh
Jika pengusaha memiliki kepentingan, begitu juga dengan pekerja. Pada dasarnya kepentingan pekerja
cenderung lebih sederhana dari pengusaha, di Indonesia istilah sekedar menyambung hidup nampaknya
tidak berlebihan disematkan untuk para pekerja. Meski begitu tanggungjawab mereka sebagai mesin
perusahaan sangat krusial, karena seberapapun besar investasi pengusaha jika tidak memiliki pekerja maka
tidak akan berarti apa – apa.
Lebih rinci, berikut kepentingan pekerja atas perusahaan sebagaimana yang dapat juga diartikan makna
penting perusahan bagi pekerja (Sumanto: 13):
1. Sumber kesempatan kerja;
2. Sumber penghasilan;
3. Sarana memperkaya pengalaman dan meningkatkan keahlian serta ketrampilan kerja;
4. Sarana mengembangkan karier;
5. Sarana mengaktualisasi diri (melalui keberhasilan kerja).
1. Peranan Pemerintah
Pemerintah sebagai agen negara yang paling otoritatif – berkuasa, tentunya mempunyai tanggungjawab
untuk mengantarkan terwujudnya cita – cita negara. Karenanya, pemerintah semestinya hadir dalam
seluruh aspek kehidupan, semisal dari mengurus kelahiran sampai menghantarkan kematian. Terlebih
dalam konteks negara demokrasi dimana kebebasan, persamaan dan keadilan menjadi isu yang kerap hadir
bahkan tidak jarang bergulir menjadi “bola liar” yang boleh jadi menghantam satu sama lain. Maka dalam
kondisi ini peran pemerintah menjadi mutlak sebagai dinamisator untuk membangun harmoni.
Dari berbagai macam aspek kehidupan, fenomena ketenagakerjaan dalam hubungan industrial menjadi
salam satu dinamika yang menarik untuk dikaji. Pasalnya, pengusaha pada satu sisi tidak jarangan
70
berhadapan dengan pekerja pada sisi lainnya. Konflik kepentingan dalam hubungan industrial memang
bukan persoalan baru, sebutsaja pertentangan antara kelas borjuis melawan kelas proletar yang
memperebutkan sumber – sumber ekonomi yang kemudian ditangkap oleh Teori Kelas Marxisme bahwa
sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas.
Pertentangan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja, didasarkan oleh perbedaan kepentingan diantara
keduanya yang mana hal tersebut ditentukan oleh kedudukan masing – masing dalam proses produksi. Hal
inilah yang kemudian menurut Karl Marx menyebabkan masing – masing pihak mengambil sikap yang
berbeda dalam perubahan sosial, dimana pengusaha akan bersifat konservatif dan pekerja bersikap
revolusioner dalam pengertian pengusaha sebisa mungkin mempertahankan status quo sedangkan buruh
berkepentingan melakukan perubahan. Maka dalam kodisi ini pilihannya tidak lain dengan melakukan
revolusi dalam perubahan sistem sosial.
Tidak berhenti sampai disana, menurut Marx negara secara hakiki merupakan kelas yang secara langsung
maupun tidak langsung dikuasai oleh kelas yang memiliki kekuatan ekonomi/ pengusaha. Karenanya peran
negara lebih dimaknai sebagai “body guard” untuk mengamankan para pengusaha. Namun dalam persepsi
penulis, kita boleh saja setuju sebagian dan berbeda pada hal – hal tertentu atas pandangan Marx
utamanya terkait peran pemerintah dalam konteks benturan kepentingan di atas.
Kekinian, pemerintah sebagai penyelenggara negara tentunya tidak dapat serta merta dalam mengambil
kebijakan dikarenakan control publik yang begitu kuat seiring dengan perkembangan pengetahuan dan
teknologi. Oleh karena itu, peran pemerintah seyogiaya dapat dilihat lebih dari dari sekedar membangun
harmoni tetapi banyak juga banyak benefit yang dapat diambil oleh pemerintah. Sebagaimana dipetakan
oleh Simanjuntak (2003: 8 – 11) berikut ini:
Pertama, perusahaan merupakan sumber kesempatan kerja. Lapangan dan kesempatan kerja merupakan
kebutuhan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi akan dapat menimbulkan keresahan social dan
menganggu pertumbuhan ekonomi. Kredibilitas suatu pemerintahan dapat juga diukur dari
71
kemampuannya memperkecil tingkat pengangguran. Sebab itu Pemerintah selalu berkepentingan untuk
mendorong pertumbuhan dunia usaha supaya dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi angkatan
kerja yang bertambah setiap tahun.
Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak pengusaha yang
mengembangkan perusahaan atau membuka usaha baru, semakin banyak pekerja yang memperoleh
penghasilan. Semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas, semakin banyak
pekerja yang memperolej peningkatan penghasilan. Dengan demikian, pendapatan nasional akan
meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.
Ketiga, Pemerintah berkepentingan dan mengharapkan semua perusahaan dapat menjamin penyediaan
dan arus barang, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen maupun sebagai masukan
barang setengah jadi untuk perusahaan lain.
Keempat, perusahaan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, kemakmuran bangsa dan ketahanan
nasional. Pendapatan nasional adalah akumulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi membuka peluang untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengurangi ketergantungan politik dan ekonomi pada
negara lain. Pertumbuhan ekonomi akan memperkuat stabilitas masyarakat dan stabilitas politik. Sebab itu,
Pemerintah berkepentingan untuk mendorong perluasan dan pertumbuhan dunia usaha.
Kelima, perusahaan merupakan sumber devisa. Dalam globalisasi ekonomi, devisa merupakan suatu
kebutuhan negara yang sangat penting. Hasil-hasil perusahaan yang digunakan di dalam negri akan
mengurangi jumlah impor serta menghemat penggunaan devisa. Apalagi bila hasil-hasil perusahaan di
ekspor, devisa akan bertambah.
72
Keenam, keuntungan perusahaan dan pendapatan karyawannya merupakan sumber utama pendapatan
negara melalui sistem pajak. Semakin besar sisa hasil usaha atau keuntungan perusahaan, semakin besar
potensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin besar penghasilan pekerja, semakin besar pula potensi
pembayaram pajak penghasilan.
Kendati demikian dalam rangka menunjang dan mendorong keberhasilan perusahaan termasuk
didalamnya kesejahteraan pekerja, Pemerintah perlu menyusun pengaturan dan mempersiapkan
prasarana dan sarana penunjang yang dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu:
1. Prasarana dan sarana ekonomi, termasuk alat-alat perhubungan darat, laut dan udara; pelabuhan,
lapangan terbang dan pergudangan; komunikasi seperti telepon, telefax, internet, radio dan
televisi; air dan energy; jasa perbankan dan informasi; keamanan dan ketertiban, serta stabilitas
ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagian besar prasarana dan sarana ekonomi tersebut disediakan
langsung oleh Pemerintah. Sebagian lagi dapat diserahkan kepada pihak masyarakat atau dunia
bisnis seperti pelayanan komunikasi, air dan energi serta jasa perbankan;
2. Serangkaian kebijakan termasuk kebijakan di bidang produksi dan investasi, distribusi, distribusi,
fiscal dan moneter, harga dan upah, ekspor dan impor, dan lain-lain;
3. Dukungan ketenagakerjaan baik dalam bentuk penyediaan tenaga yang kompeten dan sesuai, ahli
dan terampil, maupun dalam bentuk penciptaan iklim kerja dan hubungan industrial yang kondusif
untuk bekerja secara produktif.
Secara operasional, eksistensi pemerintah sebagai regulator dalam hubungan industrial tergabung dalam
Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yang terdiri dari 3 unsur, yakni: unsur pemerintahan, organisasi pekerja,
dan organisasi pengusaha. Fungsi lembaga kerjasama Tripartit adlaah sebagaia forum komunikasi dan
konsultasi, dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap, dan rencana dalam menghadapi masalah-
masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor-faktor
yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal-hal yang akan dating (Jhon Suprihanto, 2016: 32 – 33).
Adapun dasar hukum lembaga kerjsa Tripartit adalah sebagai berikut :
• UU No.113 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Kepmenaker No. Kep. 355/Men/X/2009 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit
74
BAB II.
BENTUK HUBUNGAN INDUSTRIAL
Uraian Materi:
Bagian ini menjelaskan bentuk hubungan industrial yakni Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja
Bersama yang secara spesifik menjelaskan pengertian, kententuan yang diatur pada masing - masing
bentuk serta perbedaan diantara keduanya.
Capaian Pembelajaran:
• Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan maksud dari Peraturan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja Bersama;
• Mahasiswa diharapkan mampu memetakan berbagai ketentuan dari Peraturan Perusahaan
dan Perjanjian Kerja Bersama; dan
• Mahsiswa dapat memahami perbedaan bentuk diantara keduanya.
Bentuk hubungan industrial dimaknai sebagai sarana/alat untuk menerapkan berbagai nilai dan prinsip
dalam hubungan industrial. Sebagaimana diketahui bersama bahwa praktik hubungan industrial akan
dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal karnanya, untuk memastikan hubungan
industrial terjaga dengan baik dibutuhkan sarana sebagai aturan main yang memberikan batasan yang
tegas, utamanya terkait hak dan kewajiban para pihak. Sekurang – kurangnya terdapat dua bentuk
hubungan industrial, yakni:
75
II.1 Peraturan Perusahaan
Idealnya peraturan perusahaan lahir bersamaan dengan kehadiran suatu perusahaan yang dijadikan
landasan dalam pengelolaan usaha dan dalam kondisi ini, peraturan tentunya dibuat sepihak oleh
pengusaha. Kendati demikian aturan yang dibuat tidak dapat semena – mena, melainkan harus sesuai
dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Semisal untuk menetapkan upah, besaran upah yang
dibayarkan minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Menurut Simanjuntak (2011: 17) peraturan perusahaan memuat ketentuan antara lain mengenai:
1. Hari kerja, jam kerja dan waktu kerja lembur,
2. Waktu istirahat kerja dan cuti,
3. Skala upah, tunjangan dan bonus,
4. Program keselamatan dan kesehatan kerja,
5. Ketentuan dan tindakan disiplin,
6. Perawatan kesehatan dan pengobatan,
7. Program kesejahteraan pekerja dan keluarganya
Pada satu sisi, peraturan perusahaan mencerminkan kepentingan pengusaha dan disisi lainnya harus
mampu mengakomodir kepentingan pekerja hingga terbangun keseimbangan dari para pihak. Namun
aturan saja tidak cukup, karnanya dibutuhkan komitmen para pihak untuk menghormati dan menjalankan
kewajiban masing – masing sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan.
II.2 Perjanjian Kerja Bersama
Pada bagian ini, pertanyaan mendasar yang mungkin muncul dari pembaca adalah apa yang membedakan
antara peraturan pemerintah dengan perjanjian kerja bersama? Memang keduanya sepintas terlihat
identik, namun jika didalami terdapat perbedaaan yang mendasar. Sebelum menjelaskan perbedaan
76
sebagaimana dimaksud, sebelumnya penulis akan menjelaskan pengertian perjanjian kerja bersama
sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat 2, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.48/MEN/IV/2004
bebagaiu berikut:
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Berangkat dari definisi ini maka perbedaan antara peraturan perusahaan
dengan perjanjian kerja bersama mencakup 3 hal yakni aktor, waktu dan regulasi, berikut penjelasannya:
1. Aktor, peraturan perusahaan dibuat hanya oleh pengusaha sehingga boleh jadi kepentingan
pekerja tidak terakomodir. Sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat bersama dengan pekerja
yang dalam hal ini diwakili oleh serikat buruh.
2. Waktu, peraturan perusahaan umumnya dibuat dimasa awal operasional perusahaan/ sebelum
penerimaan pekerja meskipun ada beberapa aturan tambahan yang dibuat kemudian. Karena
perjanjian kerja bersama melibatkan pekerja, maka perjanjian dibuat setelah memiliki pekerja.
3. Regulasi, peraturan perusahaan wajib dibuat berdasarkan Pasal 2 KEP. 48/MEN/IV/2004 dimana
Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 karyawan. Sedangkan
perjanjian kerja bersama bukan suatu kewajiban, meskipun begitu menurut ketentuan pasal 15
KEP. 48/MEN/IV/2004 mereka harus memberikan respons jika Serikat Pekerja meminta adanya
perjanjian kerja bersama. Jadi, apabila Serikat Pekerja menghendaki, maka pengusaha wajib
memenuhinya.
Setali tiga uang dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dimaksudkan untuk menciptakan
hubungan industrial yang harmonis antara Pengusaha dengan Pekerja melalui pengaturan hak dan
kewajiban yang jelas. Karena bagaimanapun keduanya ada dalam ikatan mutualisme, pekerja
membutuhkan pengusaha sebagai sumber mata pencaharian sedangkan pegusaha membutuhkan pekerja
sebagai mesin yang menggerakan perusahaan. Perjanjian kerja bersama akan memberikan ruang negosiasi
bagi para pihak, untuk menghindari proses yang intimidatif antara satu sama lain yang pada gilirannya
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan antara keduanya.
77
Selain itu juga, perjanjian kerja bersama merupakan alat perlindungan bagi pekerja terutama yang berada
di level bawah. Seperti diketahui, perjanjian kerja bersamabiasanya diberlakukan untuk karyawan level
bawah seperti clerck, messenger, atau office boy yang mempunyai posisi tawar relative rendah. Dengan
adanya perjanjian kerja bersama ini posisi mereka menjadi lebih terlindungi. Untuk pekerja di level yang
lebih tinggi karena kemampuan yang mereka miliki. Mereka biasanya mempunyai perjanjian yang sifatnya
individual dengan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Walaupun ada juga perusahaan yang
mengatur bahwa perjanjian kerja bersama berlaku untuk semua golongan pekerja (Iftida Yasar, 2010: 5 –
6).
Shaw menyatakan bahwa perjanjian perusahaan sejatinya menawarkan kesempatan untuk mencapai
fleksibilitas, peningkatan kualitas, mendorong kualitas kerja, konsensi antara manajemen dan karyawan,
dan budaya kerja sama di tempat kerja, dengan melebarkan lingkup partisipasi karyawan dalam proses
pengambilan keputusan Wahyu Ariani (2016: 3.7). masih dalam rujukan yang sama, Menurut Barbash
terdapat 5 hal yang diatur dalam perjanjian kerja bersama untuk pekerja, yakni:
1. harga karyawan ( upah dan metode penentuan upah);
2. Penggunaan tenaga kerja ( klasifikasi, masa kerja, usaha, dan jam kerja);
3. Hak kerja karyawan (hak yang diperoleh karyawan di tempat kerja sesuai dengan perjanjian kerja
bersama);
4. Hukum institusional serikat pekerja dan manajemen; dan
5. Administrasi dan pelaksanaan perjanjian.
78
BAB III.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Uraian Materi:
Bab ini menjelaskan gagasan utama dari paham liberalisme dan sosialisme yang diturunkan kedalam
konsep hubungan industrial, disamping itu bab ini juga diperkaya dengan pandangan/ gagasan –
gagasan Agama Islam dalam menyoal hubungan industrial.
Capaian Pembelajaran:
• Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan gagasan utama dalam paham liberalisme dan
sosialisme beserta relevansinya terhadap hubungan industrial;
• Mahasiwa dapat mengetahui berbagai gagasan dalam Agama Islam terkait hubungan
industrial.
III.1 Liberalisme
79
Istilah liberal berasal dari kata latin yakni: “liber” yang berarti kebebasan. Dalam paham ini kebebasan
merupakan prinsip yang mendasar dan bisa juga dimaknai sebagai kebutuhan yang paling utama jika
dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Karena itu kebebasan merupakan fondasi bagi pemikiran liberal,
dimana pangkal dari kebebasan terletak pada setiap pribadi/individu. Artinya, kemajuan sebuah
masyarakat, dimulai dari kemajuan individu yang berhasil mengartikulasikan nilai – nilai kebebasan dalam
wujud yang mandiri, kompetitif dan kreatif.
Memahami arti penting kebebasan bagi manusia, Clemens Recker (2011: 1 – 2) mengurai kebebasan dalam
ketiga pandangan. Pertama, Sebagian orang memberikan argumentasi berdasarkan agama bahwa Tuhan
memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas, dimana setiap upaya menghalangi kebebasan
berarti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kedua, ada juga mazhab yang menyatakan bahwa
kebebasan merupakan sifat orisinil manusia. Tidak mungkin memisahkan antara individu dengan
kebebasannya, inilah yang kemudian disebut dengan mazhab hak – hak alami dimana argumentasi
kebebasan dalam mazhab initidak didasarkan agama. Dimana mereka menjadikan hak – hak alami sebagai
argumentasi tertinggi an paling utama disbanding hak – hak yang ditentukan oleh berbagai aturan dan
konvensi yang dibuat oleh manusia itu sendiri.
Ketiga, utilitarianisme yang menegaskan bahwa sistem sosial, politik dan pasar yang dibangun di
ataspondasi kebebasan lebih banyak memberkan manfaat bagi kemanusiaan. Dimana kebebasan itu sendiri
mendorong manusia untuk bersaing secara individual dan saling meningkatkan kecerdasan manusia.
Mendekati paham liberalisme dalam kaitannya dengan hubungan industrial, bagi paham ini pemerintah
harus hadir baik dalam bentuk aristokrasi, demokrasi atau pemerintahan individu. Kehadiran pemerintah
dalam berbagai ruang, termasuk juga didalam hubungan industrial harus dalam batasan yang tegas.
Dimana pemerintah hanya memiliki 3 kewajiban yakni menciptakan institusi kepolisian, menegakkan
keadilan dan menjaga keamanan negara. Maka diluar konteks tersebut pemerintah tidak punya hak
melakukan intervensi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan John Stuart Mill dalam Clemens Recker (2011:
15).
80
Jika pemahaman tersebut ditarik dalam konteks hubungan industrial yang sekaligus menjadi penekanan
dalam bagian ini, maka peranan pemerintah sebagai penegak kadilan dengan penekanan kebebasan setiap
individu menjadi begitu sempit, disamping isu – isu dalam hubungan industrial yang sesungguhnya
kompleks seperti: keterpihakan, keseimbangan, harmonisasi dan lain sebagainya yang secara prinsip boleh
jadi berhadapan jika hanya menggunakan pendekatan atas nama kebebasan.
III.2 Sosialisme
Dalam Ensyclopedia Britanica, sosialisme didefinisikan sebagai ajaran sosial dan ekonomi yang
menyerukan kepemilikan atau kontrol dari publik terhadap properto dan sumber daya alam.
Menurut Cole (1965 : 1 - 2) istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang
berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal
dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20
berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem
ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.
Dimana penggunaan istilah sosialisme itu sendiri baru dimulai awal abad ke – 19 yang dalam
bahasa Inggris digunakan untuk menyebut pengikut Robert Owen di tahun 1897, sedangkan di
Perancis digunakan untuk menyebut pemgikut Saint Simant pada tahun 1832.
Menyoal kajian dari sosialisme, tidak akan lepas dari kritik atas dampak ekonomi liberal seperti
keterbelakangan, penderitaan dan kemiskinan sebagaimana yang terjadi di negara – negara Eropa. Dimana,
golongan pengusaha (borjuis) berhasil merebut dan menguasi negara alat untuk memenuhi kepentingan
mereka. Secara prinsip, sosialisme menghendaki terwujudnya suatu masyarakat yang egaliter dengan
menyerahkan sepenuhnya hak – hak atas barang barang produksi dimiliki oleh negara bukan perseorangan.
Oleh karenanya, segala sesuatu yang diproduksi oleh siapapun dimaknai sebagai produk sosial dan para
pihak yang berkontribusi atasnya memiliki hak atas produk tersebut. Maka yang berlaku pada kontes ini
masyarakat harus memiliki kontrol atas kepemilikan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian,
masyakarat akan merasakan kebebasan dan kesetaraan yang sesungguhnya bukan kebebasan individu
sebagaimana yang dimaksud oleh paham liberal.
81
Maka relevansi dengan hubungan industrial adalah peran pemerintah menjadi lebih dominan dalam
melakukan pengaturan dan pengawasan, yang mana hal ini berbanding terbalik dengan peran pemerintah
dalam paham liberal yang mengendaki kebebasan individu yang sedikit intervensi.
III.3 Hubungan Industrial Dalam Islam
Agama sebagai the way of life membawa tuntunan kesemua aspek kehidupan, termasuk juga menyoal
hubungan industrial, dalam islam pola hubungan ini diatur baik dalam Al qur`an maupun Hadist Nabi
Muhammad S.A.W. Pada konteks pekerjaan, Nabi Muhammad mengapresiasi mereka yang bekerja dengan
tangannya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Muslim RA. berikut: “Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak kemudian
mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada
orang kaya, diberi atau ditolak”.
Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa: “Tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang
dihasilkan tangannya. Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan
pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah” (HR. Ibnu Majah). Dalam Al Qur`an Surat At Taubah Ayat
105, Allah S.W.T berfirman yang artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang – orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu dibertakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Menurut Mubyarto dalam buku yang berjudul Etika, Agama dan Sistem Ekonomi (2002), etika bisnis dalam
Islam mencakup 4 hal, yakni:
1. Kesatuan (Unity);
2. Keseimbangan (Equilibrium);
3. Kebebasan (Free Will); dan
4. Tanggungjawab (Responsibility).
Berikut penjelasan yang coba penulis pahamai dari ke-empat hal dimaksud. Pertama, Kesatuan. Kesatuan
yang dimaksudkan dalam hubungan indusrtrial, hendaknya para pihak bersinergi satu sama lain. Dalam
82
berdinamika konflik pasti ada, namun Islam mengajarkan hendaknya mencari solusi dengan jalan terbaik.
Justifikasinya, dalam Al Qur`an Surat Ali Imran Ayat 103: “Dan berpeganglah kalian kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah bercerai – berai. Kedua, Keseimbangan. Keseimbangan dimaksud adalah bagaimana
para pihak dapat mengambil peran masing – masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
dimilikinya. “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS Al-An’am: 132).
Keseimbangan juga dapat bermakna, bahwa aktifitas duniawi tidak semata – mata mengenyampingkan
nilai – nilai akhirat. Ketiga, Kebebasan. Maka dalam konteks ini, Islam membawa kegagasan terkait
kebebasan dan persamaan. Karnanya dikotomi pekerja dan pengusaha lebih dimaknai sebagai relasi
pekerjaan semata, tidak kemudian memposisikan yang satu lebih baik disbanding dengan yang lainnya.
Dalam Al Qur`an Allah S.W.T berfirman: “ …, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi
Allah ialah orang yang laing taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha
mengenal”.
Keempat, Tanggungjawab. Bagi seorang pekerja yakni menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan maksimal
merupakan perkara yang dicintai oleh Allah S.WT. Karenanya, pekerja harus kooperatif dalam dalam
sebuah sistem dengan menyelesaikan tanggungjawabnya seoptimal mungkin. Hal ini sejalan dengan Hadist
yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi dari Aisyah R.A. berikut: “Sesungguhnya Allah mencintai
seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara professional”. Sedangkan tanggungjawab pada
level pengusaha, mereka harus memperhatikan hak – hak pekerja termasuk soal ketepatan waktu
pembayaran. Justifikasinya, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.
Ibnu Majah). Bahkan dalam hadist yang lain, disebutkan menunda kewajiban itu termasuk kedzalima (HR.
Bukhari dan Muslim).
83
BAB IV.
PARADIGMA BARU HUBUNGAN INDUSTRIAL
Uraian Materi:
Dalam bab Paradigma Baru Hubungan Industrial, akan dijelaskan konsep Hubungan Industrial
Pancasila yang mencakup: nilai – nilai yang terkandung didalamnya, gagasan Hubungan Indutrial
Pancasila bagi Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah serta urgensi penerapan Hubungan Industrail
Pancasila. Disamping itu, Bab ini juga memuat gagasan – gagasan kedalam 4 dimensi yang menandai
paradigma baru dalam Hubungan Industrial Pancasila.
Capaian Pembelajaran:
• Mahasiwa diharapkan mampu menjelaskan konsep Hubungan Industrial Pancasila;
• Mahasiwa dapat memahami gagasan pokok dalam Hubungan Industrial Pancasila; dan
• Mahasiswa diharapkan mengetahui paradigma baru dalam Hubungan Industrial Pancasila.
IV.1 Hubungan Industrial Pancasila
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ideologi dan paham – paham keagamaan sesungguhnya
berpengaruh terhadap corak hubungan kerja dalam masyarakat maupun perusahaan. Para pihak akan
berusaha menentukan batasan – batasan dalam membangun keharmonisan berdasarkan apa yang mereka
yakini. Begitujuga dengan Pancasila sebagai ideologi dan paham negara, internalisasi nilai berjalan baik
secara alamiah maupun dalam agenda negara ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
termasuk didalamnya soal hubungan industrial.
84
Pada kasus hubungan industrial, maka kemudian lahirlah konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang
mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa perjuangan
dan mempertahankan kemerdekaan pola hubungan industrial lebih kentara nilai sosial politik daripada
ekonomi karena memang sebagian besar aktifitas usaha ketika itu merepresentasikan kekuatan kolonial.
Isu yang mengisi ruang dialektikapun seputar persamaan hak, penolakan atas intimidasi pekerja disamping
juga diarahkan dalam rangka merebut kemerdekaan.
Hari berganti musim, hubungan industrial terus menggeliat hingga sampai pada Orde Baru barulah konsep
HIP dan mengisi dialektika ketenaga kerjaan di Indonesia. Tidak sulit bagi kita untuk menterjemahkan
pengertian dari HIP, namun yang masih menjadi pekerjaan rumah hari ini HIP dalam praktik
ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Fenomena mogok - boikot kerja dan perlakuan
semena – mena para majikan menggambarkan konflik dan disharmoni para pihak yang tidak pernah surut.
HIP merupakan hubungan industrial yang berlandaskan nilai – nilai dari Pancasila. Dalam Seminar Nasional
Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarkan pada tahun 1974 dikemukakan tujuan Hubungan
Industrial Pancasila “Mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus
1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan
Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha,
meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat
manusia.” Maka penulis membuat simplikasi nilai – nilai yang terkandung didalam HIP mencakup 5 nilai
yang mengikuti setiap sila dari Pancasila, yakni:
1. Ketuhanan (dapat juga dimaknai dengan kebudayaan);
2. Kemanusiaan;
3. Persatuan;
4. Musyawarah; dan
5. Keadilan.
85
Merujuk kepada nilai – nilai dari Pancasila diatas, maka seyogianya para pihak dalam HIP perlu
memperhatikan beberapa gagasan pokok yang penulis kategorikan kedalam 3 unsur. Pertama, unsur
pengusaha. Pengusaha harus mampu memandang pekerja sebagai mitra, karena bagaimanapun
perusahaan tidak dapat berjalan tanpa mereka. Pekerja sebagai mitra mengandung makna bahwa mereka
memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang perlu dijaga. Disamping itu, pengusaha sebagai
pengambil kebijakan tidak tapat semena – mena, mereka harus membuka ruang dan mengutamakan
musyawarah untuk mufakat.
Kedua, unsur pekerja. Sebagai pekerja kerja mereka harus memahami bahwa bekerja bukan sekedar
mengejar materi, lebih dari itu bekerja merupakan sarana pengabdian kepada bangsa dan negara yang
secara bersamaan bernilai ibadah. Karena itu, setiap persoalan yang mungkin hadir dalam dunia kerja
hendaknnya diselesaikan daengan jalan yang baik dan menghindari anarkisme. Ketiga, unsur pemerintah.
Pemerintah memegang peranan yang penting dalam membumikan nilai – nilai Pancasila dalam HIP, maka
pemerintah sebagai pengayom seyogianya dapat berlaku adil kepada kedua belah pihak dalam menjaga
persatuan dan membangun keharmonisan dengan mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan dan gotong
royong.
Menurut Sumanto (2013: 131 – 132) urgensi pengembangan HIP bagi pemerintah Orde Baru dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa pemerintah Orde Baru jelas bertekad menerapkan Pancasila dan UUD 1945 di setiap aspek
kehidupan bangsa. Ini berarti tata kehidupan dan pergaulan di tempat kerja harus ditata sesuai
dengan isi dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa dalam sejarah sebelum pemerintah Orde Baru telah diterapkan sebagai sistem hubungan
perburuhan, baik yang berdasarkan paham demokrasi liberal maupun yang berdasarkan ajaran
komunis, asaz - asaz perburuhan pada masa orde lama selalu berusaha mempertahankan dan
memetingkan masing-masing pihak (pekerja dan pengusaha). Karena masing-masing pihak saling
menonjolkan kepentingannya masing-masing, maka disana selalu terdapat adu kekuatan dalam
menyelesaikan perselisihan. Tidak jarang pada masa itu dijumpai pemogokan sebagai senjata para
pekerja dan lock out sebagai senjata para pengusaha. Di samping itu, pada masa-masa pergerakan
kemerdekaan praktik - praktik hubungan perburuhan di Indonesia banyak berhubungan dengan
86
kegiatan politik dari pada ekonomi. Hal ini terbukti dari gerak serikat pekerja yang banyak terlibat
dalam berbagai kegiatan politik negara.
3. Bahwa karena pembangunan ekonomi itu memerlukan suasana yang stabil baik politik maupun
keamanan maka perlu adanya jaminan ketenagan kerja dan usaha agar proses produksi pun juga
stabil. Ketenangan kerja dan ketenangan usaha itu akan terjadi di setiap tempat kerja apabila ada
suatu tata kehidupan dan pergaulan yang baik harmonis dan dinamis.
4. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka pemerintah Orde Baru mengembangkan suatu hubungan
industrial yang disebut Hubungan Industrial Pancasila. Sebagai tindak lanjut dari pengembangan
HIP maka pada bulan Desember 1974 dilakukan pertemuan dalam bentuk seminar yang dihadiri
para pengusaha, pemerintah, wakil-wakil serikat pekerja, kalangan perguruan tinggi untuk
membuat consensus, yaitu menetapkan pokok-pokok HIP dan mereka juga bersepakat untuk
melaksanakan HIP. Sedangkan sebelumnya (tahun 1973) dibentuk Federasi Buruh Seluruh
Indonesia (FBSI). Melalui berbagai kegiatan pertemuan, seminar, diskusi, lokakarya maka
dilanjutkan terus pengembangan konsep HIP tersebut sehingga pada tahun 1978 keluar TAP MPR
No.11 tentang P4. Konsep HIP yang telah dirintis mendapat dukungan yang kuat. Namun dalam
perjalanan pelaksanaannya dijumpai berbagai hambatan tentang kesepakatan istilah-istilah
maupun perbedaan penafsiran konsep HIP. Pada tahun 1985 dilakukan penyempurnaan dalam
peristilahan dan system diklat penyuluhannya. Salah satu hasil yang penting adalah dengan
dikeluarkannya pedoman pelaksanaan HIP dalam praktik hubungan industrial sehari-hari.
Karena HIP mempunyai makna penting untuk dilaksanakan, operasionalisasi HIP memiliki landasan agar
menjadi konsep yang futurustik. Masih dalam rujukan yang sama, maka berikut dibawah ini landasan yang
digunakan dalam Hubungan Indistrial Pancasila:
1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila yang artinya sila-sila dari Pancasila harus ditafsirkan dan diterapkan
secara terkait satu sama lain secara bulat dan utuh. Jadi semua perilaku yang terlibatdalam
hubungan industrial (pengusaha buruh dan pemerintah) wajib berpedoman pada nilai-nilai
Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa.
2. Landasan Hukum (Konstitusional), yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan hukum
sekaligus sumber hukum HIP. Sebagai sumber hukum atau hukum dasar artinya segala perundang-
undangan peraturan dan hal yang sifatnya mengatur kehidupan HIP haruslah berpedoman pada
hukum dasar tersebut.
87
3. Landasan Struktural dan TAP MPR No 11 artinya dalam pola struktur pelaksanaan HIP bedasarkan
dan mengacu pada P4.
4. Landasan Operasional: Garis-garis Besar Haluan Negara serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya
yang diatur oleh pemerintah di dalam program pembangunan.
5. Hubungan Industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah
untuk menciptakan keamanan nasional, stabilitas nasional, meningkatnya partisipasi social dan
kelanjutan pembangunan nasional.
IV.2 Paradigma Baru Hubungan Industrial
Jika dialektika HIP dimulai pada masa Orde Baru, maka paradigma baru hubungan industrial dimulai pasca
reformasi di tahun 1998. Sebagaimana kita ketahui bersama gelombang reformasi membawa perubahan
yang signifikan terhadap perubahan ketatanegaraan di Indonesia yang mengakar kepada tututan
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. Kondisi ini tentunya secara
sadar maupun tidak akan berdampak kepada perubahan pola hubungan industrial.
Maka pada bagian ini, penulis akan memetakan beberapa perubahan pola yang terjadi pada era kekinian
yang sekaligus menandai paradigma baru dalam hubungan industrial di Indonesia kedalam 4 dimensi
sebagaimana berikut ini:
1. Dimensi Kelembagaan;
2. Dimensi Partisipasi;
3. Dimensi Keberlanjutan; dan
4. Dimensi Regulasi.
Pertama, dimensi kelembagaan. Pada dimensi ini perubahan pola sangat kentara dengan munculnya
berbagai serikat pekerja sebagai konsekuensi euphoria reformasi. Simanjuntak (2011: 23) menyebutkan
pasca reformasi telah terbentuk lebih dari 100 serikat pekerja. Artinya, saluran – saluran dalam
memperjuangkan aspirasi pekerja menjadi lebih banyak dan kompleks yang membedakan paradigma lama
dalam hubungan industrial. Fenomena ini tentunya dapat berdampak ganda, argumentasi yang posisif akan
mengapresiasi kondisi ini karena kepentingan pekerja akan banyak diperjuangkan melalui serikat – serikat
yang ada. Sedangkan argumentasi yang negatif, akan menuduh bahwa serikat pekerja dapat ditunggangi
88
kepentingan pribadi/ kelompok. Karena itu peran pemerintah diperlukan, untuk memastikan agar serikat –
serikat yang ada dapat bernilai positif untu kebaikan para pihak.
Kedua, dimensi partisipasi. Kemunculan berbagai serikat pekerja, sedikit banyak dapat dimaknai sebagai
perluasan partisipasi pekerja. Terlebih hari ini, ketika teknologi komunikasi dan informasi berkembang
sedemikian pesat menakibatkan pekerja lebih kritis menyoroti berbagai persoalan yang terjadi yang
sekaligus menandai paradigma baru dalam hubungan industrial. Lebih dari itu, bentuk kritisi hari ini dapat
dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang dengan singkat dapat menarik perhatian publik yang
menjadi modal awal dalam membangun negosiasi dengan para pengusaha.
Ketiga, dimensi keberlanjutan. Jika kedua dimensi sebelumnya ditujukan untuk para pekerja, maka dimensi
keberlanjutan sebagai paradigma baru hubungan indusatrial dapat diartikulasikan kedalam bentuk
tantangan bagi kedua belah pihak. Untuk pengusaha, keberlanjutan usaha mereka hari ini tergantung
bagaimana pengusaha dapat bertahan ditengah gerakan pekerja yang lebih sistematis dan massif serta
yang lebih penting adalah pengusaha harus mampu bertahan dari perekonomian nasional yang labil dan
fluktuatif. Untuk pekerja, tantangan keberlanjutan mereka pasca reformasi adalah isu outsourcing
sebagaimana dalam UU. No. 13 Tahun 2003. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim
perekonomian yang kondusif demi terjaganya keberlanjutan perusahaan.
Keempat, dimensi regulasi. Dari pemerintah untuk pekerja, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau
Internasional Labour Organization ( ILO ) pada tahuhn 1998 mengeluarkan Deklarasi yang pada intinya
mewajibkan semua negara di dunia meratifikasi dan menerapkan prinsip dari 8 Konvensi Dasar ILO. Dua
diantaranya, yaitu Konvensi No.87 dan No.98 menyangkut kebebasan berserikat dan perlindungan hak
untuk bernegosiasi. Ratifikasi kedua Konvensi tersebut juga berarti membuka peluang dan perlindungan
bagi para pekerja untuk membentuk serikat pekerja (Simanjuntak, 2011: 23). Dari pemerintah untuk
pengusaha, pemerintah harus menerapkan kebijakan afirmatif, dengan memberi perlindungan kepada para
pengusaha terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean dengan cara: kemudahan pengurusan izin,
melakukan pengawasan terhadap pungutan liar, fasilitasi permodalan dan juga mengatur arus barang
masuk sehingga tidak mematikan produksi dalam negeri.
90
Pedoman Hubungan Industrial Pancasila
Menelisik rumusan hubungan industrial, sekurangnya dapat disandarkan pada konsep hubungan
perburuhan (labor relation) yang mulanya menyoal dinamika hubungan antara pekerja dan
pengusaha dalam ruang lingkup yang terbatas. Merespon perubahan yang begitu cepat kemudian
berimplikasi kepada meningkatnya tuntutan serta standart kehidupan yang semakin tinggi,
sehingga hal tersebut membawa dinamika perburuhan menjadi semakin kompleks kedalam
berbagai aspek kehidupan. Sosial ekonomi, politik dan budaya kemudian menjadi bagian yang
tidak terpisahan dalam kajian hubungan perburuhan yang secara otomatis “menyeret”
pemerintah kedalam isu ini.
Maka dengan alasan tersebut hubungan perburuhan kemudian bertransformasi menjadi
hubungan industrial dengan penekanan atas interaksi dari pengusaha, pekerja dan pemerintah
dalam membangun ikatan yang harmonis dengan mengakomodir kepentingan para pihak.
Argumentasi ini sejalan dengan definisi hubungan industrial sebagaimana menurut para ahli
berikut ini: Menurut McMillan dalam Umar Hasan, hubungan industrial merupakan interaksi
antara para majikan, para pegawai, pemerintah dan asosiasi – asosiasi lewat mana mediasi dari
interasi tersebut dilakukan. (Umar Hasan, 2013: 4). Sedangkan menurut Sumanto (2013: 11)
hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun
jasa (pengusaha), pekerja/serikat pekerja, dan pemerintah. Dimana hubungan industrial bertujuan
untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pihak-pihak tersebut.
Untuk terbangun pola yang harmonis dalam hubungan industrial, karenanya interaksi diantara
para pihak harus memperhatikan beberapa asaz sebagai berikut (Sumanto 2013: 16 - 17):
4. Asas Partner in Production
Menurut asas ini, buruh dan pengusaha mempunya kepentingan yang sama untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh mampu meningkatkan hasil usaha/produksi. Oleh
91
karena itu masing-masing pihak merupakan kawan dalam meningkatkan kesejahteraan
buruh dan meningkatkan hasil produksi.
5. Asas Partner in Profit
Menurut asas ini, hasil yang dicapai perusahaan itu seharusnya bukan untuk dinikmati oleh
pengusaha saja, tetapi harus dinikmati oleh buruh yang turut serta dalam mencapai hasil
produksi tersebut sehingga peningkatan kesejahteraan social para pekerja di perusahaan
sejalan dengan peningkatan hasil produksi.
6. Asas Partner in Responsibility
Menurut asas ini, buruh dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama
dalam meningkatkan hasil produksi. Rasa tanggung jawab kedua belah pihak ini akan
mendorong peningkatan hasil produksi.
Pada konteks umum, yang terjadi diberbagai belahan dunia bahwa corak hubungan kerja dalam
sebuah tatanan masyarakat sangat kental nuasa ideologis dari negara yang bersangkutan. Dimana
mereka membangun batasan – batasan hubungan industrial sesuai dengan apa yang mereka
yakini sebagai sebuah nilai fundamental. Semisal corak hubungan industrial dinegara kapitalis,
pasti berbeda dengan negara penganut paham sosialis, meskipun dapat kita pahami batasan
ideologi didunia dewasa ini semakin kabur.
Tidak urung yang terjadi di Indonesia dimana hubungan industrial memiliki warna tersendiri. Suatu
pola yang sejalan sebagun dengan ideologi negara yakni Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang
mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa
perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan pola hubungan industrial lebih kentara nilai sosial
politik daripada ekonomi karena memang sebagian besar aktifitas usaha ketika itu
merepresentasikan kekuatan kolonial. Isu yang mengisi ruang dialektikapun seputar persamaan
hak, penolakan atas intimidasi pekerja disamping juga diarahkan dalam rangka merebut
kemerdekaan.
Istilah HIP itu sendiri baru familiar menjadi sebuah konsep pada era Orde Baru, sederhananya HIP
merupakan hubungan industrial yang berlandaskan nilai – nilai dari Pancasila. Dari pemahaman
92
tersebut maka penulis membuat simplikasi nilai – nilai yang terkandung didalam HIP mencakup 5
nilai yang mengikuti setiap sila dari Pancasila, yakni:
6. Ketuhanan;
7. Kemanusiaan;
8. Persatuan;
9. Musyawarah; dan
10. Keadilan.
Dalam Seminar Nasional Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarkan pada tahun 1974
dikemukakan tujuan Hubungan Industrial Pancasila “Mengemban cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social melalui
penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan
produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat
manusia.”
Dalam seminar yang sama, sebagaimana dikutip oleh Soetrisno dalam Rika Jamin M. dkk pada USU
Law Journal Vol. 5 No. 1 (Januari 2017) bahwa seminar tersebut mengambil keputusan antara lain
ditentukannya sarana dalam pelaksanaan hubungan perburuhan Pancasila (yang kemudian
menjadi HIP) yaitu:
1. Lembaga kerjasama tripartit dan bipartit;
2. Perjanjian perburuhan (collective labour agreement);
3. Lembaga peradilan perburuhan;
4. Peraturan perundangan perburuhan;
5. Pendidikan perburuhan;
6. Beberapa masalah khusus.
93
Merujuk kepada nilai – nilai dari Pancasila dan sarana dari HIP diatas, maka seyogianya para pihak
dalam HIP perlu memperhatikan beberapa pedoman untuk tercapainya tujuan dari HIP itu sendiri
yang secara spesifik penulis masukan kedalam 3 unsur berikut:
Pertama, unsur pengusaha. Pengusaha harus mampu memandang pekerja sebagai mitra,
karena bagaimanapun perusahaan tidak dapat berjalan tanpa mereka. Pekerja sebagai
mitra mengandung makna bahwa mereka memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk
Tuhan yang perlu dijaga. Disamping itu, pengusaha sebagai pengambil kebijakan tidak
tapat semena – mena, mereka harus membuka ruang dan mengutamakan musyawarah
untuk mufakat.
Kedua, unsur pekerja. Sebagai pekerja kerja mereka harus memahami bahwa bekerja
bukan sekedar mengejar materi, lebih dari itu bekerja merupakan sarana pengabdian
kepada bangsa dan negara yang secara bersamaan bernilai ibadah. Karena itu, setiap
persoalan yang mungkin hadir dalam dunia kerja hendaknnya diselesaikan dengan jalan
yang baik dan menghindari anarkisme. Pasalnya jika terjadi caos bukan hanya pengusaha
yang dirugikan, pekerja juga pasti terkena dampaknya.
Ketiga, unsur pemerintah. Pemerintah memegang peranan yang penting dalam
membumikan nilai – nilai Pancasila dalam HIP, maka pemerintah sebagai pengayom
seyogianya dapat berlaku adil kepada kedua belah pihak dalam menjaga persatuan dan
membangun keharmonisan dengan mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan dan gotong
royong.
94
Daftar Pustaka
Hasan, Umar. Manajemen Hubungan Industrial. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2013. Suwarto. Hubungan Industrial Dalam Praktek. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia,
2003. Jamin M, Rika dkk. LEMBAGA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT PERUSAHAAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN DELI SERDANG. USU Law Journal. Vol. 5 No. 1 (Januari 2017)