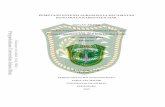TRADISI SEDEKAH BUMI DI KECAMATAN KARANGAMPEL ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of TRADISI SEDEKAH BUMI DI KECAMATAN KARANGAMPEL ...
i
Fuadul Umam
TRADISI SEDEKAH BUMI DI KECAMATAN KARANGAMPEL
KABUPATEN INDRAMAYU Kajian Filosofis Semiotik
ii
Tradisi Sedekah Bumi di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Fuadul Umam xxx + 88 halaman; 13 x 20 cm ISBN: Penulis: Fuadul Umam Tata Letak: Sam Sija Perancang Sampul: Ali Adhim Cetakan Pertama, Oktober 2019 Diterbitkan oleh: PENERBIT ARAHBACA (Kelompok Penerbit Galiung) Malang - Indonesia Telp: +6282244848787 Email: [email protected] Copyright 2019 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
iii
DAFTAR ISI
Daftar Isi ....................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................ 1 A. Latar Belakang ...................................................................... 1
BAB II AGAMA DAN BUDAYA LOKAL ..................... 5 A. Agama dan Budaya ............................................................. 5 B. Budaya ....................................................................................... 11 C. Hubungan Agama dan Budaya ...................................... 15 D. Interaksi Islam dan Budaya Lokal ............................... 19 E. Tradisi Sedekah Bumi ....................................................... 24
BAB III SEDEKAH BUMI DI DESA KAPLONGAN LOR ........................................................ 35 A. Gambaran Lokasi Penelitian .......................................... 35 B. Prosesi Acara Sedekah Bumi di Desa
Kaplongan Lor ....................................................................... 46
BAB IV ANALISIS MAKNA DAN SIMBOL SEDEKAH BUMI ........................................................... 55 A. Makna Sedekah Bumi ........................................................ 55 B. Sedekah Bumi Sebagai Bentuk Tradisi
Islam Nusantara ................................................................... 74 C. Tahlil .......................................................................................... 76 D. Kenduri ..................................................................................... 80 E. Ziarah ......................................................................................... 84
TENTANG PENULIS ..................................................... 88
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan
yang ditakdirkan untuk patuh pada peraturan alam dan terikat pada interaksi alam dan lingkungan sosial budayanya dimanapun ia berada. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika dalam kehidupan manusia terdapat lingkaran yang saling berkaitan antara manusia, alam dan lingkungan.1
Realitas budaya Indonesia yang beragam suku, tradisi yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Hal ini terbukti dengan berbagai catatan sejarah mengenai berbagai macam upacara adat dan ritual. Kekuatan gaib tersebut ada yang dianggap menguntungkan dan merugikan. Untuk itu diyakini oleh beberapa kalangan bahwa manusia senantiasa perlu berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara ritual, ziarah, sesaji, dan kaul, termasuk pementasan seni tertentu.
1 Suratman, Dkk., Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Malang: Intermedia Malang), h. 260.
2
Di sisi lain, masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang hidup dengan berorientasi pada masa lalu. Maka, keadaan yang ada pada kehidupan saat ini merupakan peran dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur pada masa lampau. Di dalam masyarakat Jawa yang agraris, alam menjadi satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Thohir, masyarakat Jawa memahami bahwa masyarakat agraris adalah masyarakat yang memiliki konsep bahwa manusia harus tunduk atau selaras dengan alam.2 Hal ini selaras dengan konsepsi msyarakat Jawa mengenai perlunya keselarasan dengan alam. Sehingga ketika terjadi hal-hal buruk yang terjadi terhadap manusia dalam kaitannya dengan alam seperti terjadinya bencana alam atau wabah penyakit itu terjadi karena keselarasan antara manusia dan alam telah goyah dan itu karena ulah manusia sendiri yang kurang menghargai alam.
Untuk itu menjaga keselarasan hidup dibutuhkan keseimbangan dengan alam yang harus dijaga agar kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu muncul berbagai macam tradisi seperti selamatan yang diadakan secara individual seperti dalam peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian dan peristiwa lainnya, maupun upacara adat
2 Mudjahirin Thohir, Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi dan Aplikasi, (Semarang: Fasindo, 2007), h. 22.
3
yang dilaksanakan secara komunal di dalam masyarakat.
Manusia dapat melakukan sebuah tindakan sebagai wujud dari balas budi atau timbal balik yang positif pada lingkungan (alam) tempat manusia mencari penghidupan. Sebagaimana yang menjadi konsep budaya manusia yang terdiri dari gagasan, aktivitas, tindakan, dan juga wujud (sebagai benda).3 Manusia mengaktualisasikan rasa syukurnya melalui gagasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan atau aktivitas. Hal ini yang menjadi dasar masyarakat Desa Kaplongan Lor Kec. Karang Ampel mengaktualisasikan rasa syukurnya atas semua yang diberikan atau dikaruniakan Allah SWT melalui sebuah budaya sebagai cipta karya masyarakat sendiri, yaitu (Nyadran) yang kemudian diartikan sebagai sebuah aktualisasi masyarakat untuk melaksanakan sedekah bumi.
Upacara sedekah bumi yang dilaksanakan di Desa Kaplongan Lor biasa disebut dengan Nyadran. Upacara adat Nyadran diadakan satu kali dalam satu tahun sebagai ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan atas limpahan rezeki yang dianugerahkan lewat perantara alam. Hal ini seusai dengan pendapat Gesta Bayuadhi bahwa secara umum tradisi sedekah bumi (nyadran) merupakan acara adat masyarakat Jawa
3 Munandar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1998), h. 13.
4
untuk mengungkapkan secara simbolik rasa syukur manusia kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui bumi beruapa berbagai macam hasilnya.4
Tradisi merupakan unsur penting dalam konstruksi sosial masyarakat, sehingga kebudayaan merupakan cipta yang harus dijaga dan terus dilestarikan. Semakin berkembangnya teknologi serta kemajuan zaman tradisi merupakan cipta kebudayaan masyarakat yang mulai termarjinalkan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat berpola fikir empirisme. Sehingga menjadi penting adanya sebuah kajian-kajian mengenai Tradisi secara filosofis sebagai sebuah ritual yang mengandung beribu makna simbolik didalamnya.
4 Gesta Bayuadhy, Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa (Yogyakarta: Dipta, 2015), h. 82.
5
BAB II
AGAMA DAN BUDAYA LOKAL
A. Agama dan Budaya
Arti agama secara epistemologi terdapat perbedaan pendapat, diantaranya ada yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu :”a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, jadi berarti tidak kacau.5 Kata agama dalam bahas Indonesia sama dengan “diin” (dari bahasa arab) dalam bahasa Eropa disebut “religi”, religion (bahas inggris), la religion (bahas perancis), the religie (bahasa belanda), die religion (bahasa jerman). Kata “diin” dalam bahasa Semit berarti undang-undang (hukum), sedang kata diin dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.6
Cliffort Geertz mengistilahkan agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusai dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam
5 Taib Thahir Abdul Mu’in, Ilmu Kalam, (Jakarta: Wijaya, 1992), h. 112. 6 Mudjahid Abdul Manaf, Ilmu Perbandingan Agama, (Jakarta: PT. Raja Persada, 1994), h. 1.
6
pancaran faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realitas.7
Sebelum Islam masuk ke Jawa, masyarakat Jawa telah memiliki kepercayaan asli yang berkaitan dengan pemujaan arwah nenek moyang. Selain itu mereka juga yakin dengan konsep-konsep agama Hindu dan Budha. Meskipun demikian masuknya Islam dapat diterima masyarakat karena penyebaran agama yang dilakukan oleh para wali memperhatikan keadaan daerah, persoalan kemasyarakatan dan penyesuaian diri. Akulturasi antara tiga sistem kepercayaan tersebut menimbulkan dua dasar keagamaan bagi masyarakat Jawa yaitu Islam murni (santri) dan Islam Kejawen (abangan).Santri, yang memahami dirinya sebagai orang Islam atau orientasinya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam. Sedangkan abangan yakni masyarakat Jawa yang beragama Islam namun kurang memegang teguh syariat Islam. Kejawen yang sering disebut abangan dalam kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh tradisi Jawa pra-Islam. Ibadah orang abangan meliputi upacara perjalanan, penyembahan roh halus, upacara cocok tanam, dan tata cara pengobatan yang semuanya berdasarkan kepercayaan kepada roh baik dan roh jahat. Kebiasaan menyembah arwah orang mati terutama arwah para leluhur yang disebut cikal bakal, 7 Cliffort Gertz, Kebudayaan dan Agama (Yogyakarta: kanisius, 1992), h. 5.
7
pendiri desa semula, memainkan peranan yang penting secara religius diantara kaum abangan. Yang sama pentingnya ialah penghormatan kepada kuburan-kuburan suci yang disebut keramat.
Agama adalah suatu fenomena abadi manusia yang secara langsung memberikan gambaran bahwa keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas di sekelilingnya. Seringkali praktik-praktik keagamaan pada suatu masyarakat dikembangkan dari doktrin ajaran agama dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan budaya. Agama Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk mengatur manusia menuju kehidupan yang lebih baik, sehingga pemahaman terhadap agama harus dilakukan melalui pengamatan secara empiris tentang manusia itu sendiri. Tanpa memahami manusia maka pemahaman tentang agama tidak akan menjadi sempurna. Beberapa manusia dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya memberikan penekan-penekanan khusus pada aspek-aspek tertentu.
Beberapa manusia dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya memberikan penekanan-penekanan khusus pada aspek-aspek tertentu dari agamanya itu. Sebagaian ada yang menekankan pada penghayatan mistik, ada yang menekankan pada penalaran logika, penekanan aspek pengalaman ritual, dan ada juga yang menekankan pada aspek pelayanan (amal sholeh). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagaimana berikut ini:
8
a. Cara mistik. Dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, sebagian manusia cenderung lebih menekankan pada pendekatan mistikal dari pada pendekatan yang lain. Cara mistik seperti ini dilakukan oleh para sufi (pengikut tarekat) dan pengikut (kejawen). Yang maksud dengan cara mistik itu sendiri adalah suatu cara beragama pengikut agama tertentu yang lebih menekankan pada aspek pengalaman batiniah (esoterisme) dari ajaran agama, dan mengabaikan aspek pengalaman formal, struktural dan lahiriyah (eksoterisme). Pada setiap pengikut agama apapu agamanya baik agama besar atau agama lokal, selalu memiliki kelompok pengikut yang member perhatian besar pada cara beragama mistik ini. Di kalangan pengikut agama Islam dikenal dengan sufisme, di kalangan umat Katolik di kenal dengan hidup kebiaraan, begitu pula di kalangan Hindu dan Budhisme. Beragama dengan cara mistik sangat digemari oleh masyarakat berkebudayaan tertentu, yang secara kultur dominan, mereka menekankan pada hal-hal mistik tersebut, seperti sebagian masyarakat dan berkebudayaan Jawa.8 Kebudayaan Jawa adalah tipe kebudayaan yang menekankan pada hidup kerohanian bersifat esoteric dan
8 Neils Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, (Jakarta: Gajah Mada Press, 1980), h. 20.
9
menjunjung tinggi harmonitas hidup sehingga kadang kala menyebabkan terjadinya sindritisme.9
b. Cara penalaran, di samping penghayatan agama cara mistik, ada pula cara penalaran, yaitu cara beragama dengan menekankan pada aspek rasionalitas dari ajaran agama. Bagi penganut aliran ini, bagaimana agama itu harus dapat menjawab masalah yang dihadapi penganutnya dengan jawaban masuk akal. Beragama tidak selamanya harus menerima begitu saja apa yang didoktrinkan oleh pemimpin agama, mereka menyayangi interpretasi yang bebas dalam menafsirkan teks dari kitab suci atau buku-buku agama lainnya. Dari tradisi Islam umpamanya, ada kelompok yang disebut mutakalimin atau para ahli ilmu kalam, yang banyak membicarakan teologi islam dengan memakai dalil tekstual (naqli) dan dalil rasional (aqil).
c. Cara amal shalih. Cara beragama yang ketiga ini lebih menekankan penghayatan dan pengamalan agama pada aspek pribadatan, baik ritual formal maupun aspek pelayanan sosial keagamaan. Menurut kelompok ini, yang terpenting dalam beragama atau tidak ialah dalam pelaksanaan segala amalan lahir dari agama itu sendiri. Tuhan memasukkan seseorang manusia ke dalam surga
9 Dadang Kahmat, Metode Penelitian Agama Perspektif Perbandingan Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 47.
10
adalah karena amal shalih orang tersebut yang dilakukan ketika ia masih hidup. Tidak ada artinya pengakuan dan iman dalam hati kalau tidak dinyatakan dalam amal perbuatan fisik dan perwujudan materi. Dalam agama islam, kelompok ini lebih banyak mengikuti ajaran fiqih dan hukum-hukum agama mengenai tata cara amal shalih dari pada amal yang lainnya.10
d. Cara sinkretisme. Secara etimologis, sinkretisme berasal dari perkataan syin dan kretizein atau kerannynai, yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Adapun pengertiannya adalah suatu gerakan di bidang filsafat dan teologi untuk menghadirkan sikap kompromi pada hal-hal yang agak berbeda dan bertentangan. Tercatat pada abad ke-2 dan ke-4 aliran Neo Platonisme berusaha menyatukan agama-agama penyembah berhala. Selanjutnya pada masa renaisan muncul usaha untuk menyatukan antara gereja Katolik Timur dan Katolik Barat. Pernah juga muncul gerakan untuk mengawinkan antara aliran lutherian dengan aliran-aliran lain dalam Protestan. Sementara itu, dalam bidang filsafat pernah muncul usaha untuk mengharmoniskan pertentangan antara pemikiran Plato dan Aristoteles.11
10 Dadang, Metode Penelitian, h. 47. 11 Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 87.
11
Cara sinkretisme adalah cara-cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama dengan memilih-milih ajaran tertentu dari berbagai
agama untuk dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau untuk diajarkan kepada orang lain. Dalam praktiknya cara beragama sinkretisme ini dapat terjadi pada bidang kepercayaan
Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dan dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan.
B. Budaya
Kebudayaan merupakan Kebudayaan merupakan ciptaan manusia selaku anggota masyarakat, maka tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, masyarakat sebagai wadah dan pendukung dari kebudayaan.12
Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari kata ‘budh’ (bahasa sansekerta) yang berarti ‘akal’, kemudian dari budh itu berubah menjadi budhi dan jamaknya “budaya”.13 Sedangkan arti kebudayaan
12 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 187. 13 Harjoso, Pengantar Antropologi (Bandung: Bina Cipta, 1984), h. 40.
12
secara terminology para ahli berpendapat, sebagai berikut:
1. Notohamidjoyo berpendapat bahwa yang di maksud dengan kultur di sini ialah seluruh suasana hidup yang diciptakan manusia dengan menggunakan bahan alam, baik bahan alam yang ada pada manusia itu sendiri maupun yang ada di luarnya.
2. Koentjaraningrat, merumuskan bahwa kebudayaan itu keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan semua tersusun dalam kehidupan masyarakat.
Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan isitem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.14
Dalam kaitannya dengan kebudayaan Jawa, Kuntowijoyo bahkan memberikan pernyataan bahwa budaya Jawa menunjukkan sikap sinkretik terhadap pengaruh Islam akibat masih kuatnya keinginan untuk mempertahankan tradisi-tradisi pra-Islam.15
14 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Dian Rakyat, 1974), h. 193. 15 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretrasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1999), h. 236.
13
Kebudayaan memiliki tiga (3) wujud yaitu dari ide, kegiatan, dan artefak.16 Wujud ide sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Sedangkan wujud kedua berupa tindakan (aktivitas) yang merupakan tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sementara yang ketiga berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat.17
Fungsi utama kebudayaan adalah untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan cenderung bertahan apabila dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan kebudayaan masyarakat bersifat interdependensi yaitu saling ketergantungan. Perubahan pada salah satu unsur kebudayaan akan diikuti oleh unsur kebudayaan yang lainnya. Dan setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda, namun setiap kebudayaan mempunyai hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di manapun berada, yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia, kebudayaan telah lahir dahulu sebelum ada generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, dan
16 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 150. 17 Koentjaraningrat, Pengantar, h. 151.
14
kebudayaan juga mencakup aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban yang diterima atau ditolak, diizinkan atau dilarang yang berlaku dalam masyarakat tertentu.18
Unsur budaya Islam tersebar di Jawa seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Secara kelompok dalam masyarakat Jawa telah mengental unsur budaya Islam sejak mereka berhubungan dengan pedagang yang sekaligus menjadi mubaligh pada taraf penyiaran islam yang pertama kali. Pada awal interaksinya kebudayaan-kebudayaan ini akan saling mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung. Pada akhirnya kebudayaan yang berbeda ini berbaur saling mempengaruhi antara budaya yang satu dan budaya yang lain. Sehingga, saat Islam sudah memiliki banyak pengikut dan legimitasi politik yang cukup besar, dengan sendirinya kebudayaan Islam yang lebih dominan dan melebur dalam satu kebudayaan dalam satu wajah baru. Unsur kebudayaan islam itu di terima, diolah dan dipadukan dengan budaya Jawa. Karena budaya islam telah tersebar dimasyarakat dan tidak dapat di elakkan terjadinya pertemuan dengan unsur budaya Jawa.19 Agama erat kaitannya dengan simbol sebagai media penghubung antara yang Esa dengan manusia, pada 18 https://4inurrohm4.wordpress.com/2013/05/18/makalah-tentang-bertahannya-kepercayaanterhadap-objek-keramat-di-era-globalisasi/, 27 juli 2017 19 https://www.scribd.com/doc/166463341/Akulturasi-Islam-Dan-Budaya-Lokal-Dalam-RItual-Keagamaan. 27 juli 2017
15
kenyataannya seperti sholat dalam agama Islam yang merupakan gerakan simbolik untuk memuja Allah, dalam agama-agama yang lain juga terdapat simbol dalam berbagai rangkaian ritual pemujaan terhadap Tuhannya.20 Pembentukan simbol dalam agama adalah kunci yang membuka pintu pertemuan antara kebudayaan dan agama, karena agama tidak mungkin dipikirkan tanpa simbol.
Dalam prosesnya dari ajaran- ajaran kepercayaan muncul adanya ritual-ritual yang diatur oleh aturan tertentu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan atau adat tertentu suatu masyarakat. Aturan seperti ini yang mengikat masyarakat atau kelompok masyarakat untuk terus melakukannya dengan harapan jauh dari malapetaka. Mitos yang seperti ini kemudian berubah menjadi ritus yang disertai dengan penggunaan simbol dalam pelaksanaannya, simbol dalam ritus tersebut yang kemudian menjadi benda-benda yang disakralkan dalam masyarakat.
C. Hubungan Agama dan Budaya
Diskusi mengenai kebudayaan dan agama Diskusi tentang kebudayaan dan agama merupakan kajian yang menarik sepanjang masa. Banyak penelitian yang dihasilkan dari diskursus ini, mulai
20 Toyyib dan Sugiyanto, Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 94.
16
dari yang sederhana hingga kompleks. Dialektika antara agama dan budaya terjadi proses saling mempengaruhi. Pengaruh timbal balik antara ajaran agama dan budaya merupakan kenyataan yang tak terbantahkan, bahkan ikut andil dalam sebuah proses kehidupan. Dalam pandangan Clifford Geertz agama merupakan sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat. Simbol-simbol ini mempunyai makna yang diwujudkan kedalam bentuk ekspresi realitas hidupnya.21
Oleh karena itu Geertz lebih menekankan pada budaya dari dimensi agama. Dalam hal ini agama dianggap sebagai bagian dari budaya. Sehingga dalam kenyataannya, Sering kali simbol-simbol itu memiliki arti penting (urgen) dalam kehidupan masyarakat Islam Jawa, dan bahkan di sinilah letak nilai kepuasan seseorang dalam menjalankan ritual keagamaannya. Budaya dan agama kadang-kadang sulit dibedakan dalam pelaksanaan sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi pemeluknya dalam bersikap maupun bertingkah laku bahkan berpola pikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadang-kadang kurang melihat budaya-budaya masyarakat yang sudah ada.
Beberapa tokoh antropolog juga mengutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski
21 Clifford Geertz, Kebudayaan, h. 5.
17
mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:
1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi
3. Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan
4. Organisasi kekuatan politik.22
Dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, hubungan agama dan budaya seperti darah kental dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebagian besar manusia yang beragama dalam mengamalkan kehidupan yang membudaya, tidak pernah lepas dari agama.
Pencampuran antara tradisi lokal yang diwarisi dari leluhur dengan ajaran baru yang masuk di tengah-tengah masyarakat terkadang menjalin sebuah jalinan yang menciptakan sesuatu dalam bentuk yang baru. Keterkaitan dan perpaduan antara dua unsur yang berbeda ini dinamakan dengan sinkretisme.
Kelompok orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan beranggapan bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Sementara orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan, karena
22 Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, h. 22.
18
praktik agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Memang benar bahwa wahyu yang menjadi sandaran fundamental agama itu datang dari Tuhan, akan tetapi realitasnya dalam kehidupan adalah persoalan manusia, dan sepenuhnya tergantung pada kapasitas diri manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan “pemikiran intelektual” untuk memahaminya, maupun kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan. Maka dalam soal ini, menurut pandangan ini realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan, sehingga “agama mau tidak mau menjadi soal kebudayaan.23
Dalam hubungan agama dan budaya, masyarakat beragama hampir bisa kita jumpai bahwa budaya dibalut dengan agama untuk melengkapi tradisi keagamaan masyarakat seperti selametan. Koentjaraningrat berpendapat bahwa: “upacara slametan yang bersifat keramat adalah upacara slametan yang diadakan oleh orang-orang yang dapat merasakan getaran emosi keramat, terutama pada waktu menentukan diadakannya slametan itu, tetapi juga pada waktu upacara sedang berjalan.”
Clifford Geertz memulai esainya dengan menyatakan kepada kita, seperti yang tersirat dalam judul esai ini, bahwa dia tertarik kepada “dimensi
23 Musa Asy’ari, Filsafat Islam Tentang Kebudayaan,(Yogyakarta: LESFI,1999), h. 75.
19
kebudayaan” agama. Di sini dia juga menjelaskan dengan baik tentang apa yang dia maksud dengan kebudayaan tersebut. Kebudayaan digambarkannya sebagai “sebuah pola makna-makna (a pattern of meanings) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu. Karena dalam satu kebudayaan terdapat bermacam-macam sikap dan kesadaran dan juga bentuk-bentuk pengetahuan yang berbeda-beda, maka di sana juga terdapat “sistem-sistem kebudayaan” yang berbeda-beda untuk mewakili semua itu. Seni bisa berfungsi sebagai sistem kebudayaan, sebagai seni juga bisa menjadi anggapan umum (commonsense), ideologi, politik dan hal-hal yang senada dengan itu.24
D. Interaksi Islam dan Budaya Lokal
Dalam pembahasan ini digunakan istilah Islam sebagai sebuah ajaran dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi dan Rosul-Nya termasuk Nabi Muhammad. Adapun manifestasi dari penganut ajaran Islam digunakan istilah ke-Islaman. Hal ini untuk membedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran dan Islam sebagai sebuah pemahaman dari penganut
24 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, 1996), h. 342.
20
agama Islam dan kebudayaan yang teraktualisasi secara nyata dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu.25
Agama, juga dalam hal ini merupakan setiap sistem kepercayaan yang mengasumsikan kemutlakan, sekurang-kurangnya berkenaan dengan pokok-pokok ajarannya. Sebab hanya dengan kemutlakannya itu maka suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang memerlukan kadar kepastian yang tinggi dan memberi kepastian, itulah fungsi pegangan atau tuntunan. Karena segi kemutlakan yang membawa serta kepastian itu maka setiap penganut suatu agama tentu menganggap bahwa agamanya adalah sesuatu yang tidak berasal dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam berbagai konsep terutama konsep tentang wahyu (revelation) pengungkapan, penjelmaan, wangsit dan lain-lain yaitu konsep-konsep yang membawa konsekuensi pandangan bahwa agama adalah ahistoris, normtaif dan menganggap bidang-bidang yang termasuk di dalam kategori “apa yang seharusnya“.
Di samping itu, pada waktu yang sama setiap penganut suatu agama berkeyakinan bahwa agamanya mengajarkan tentang amal perbuatan praktis dan itu berarti bahwa agama mengandung unsur-unsur yang
25 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 328.
21
berbeda dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sekarang, “daya dan kemampuan manusia“ adalah dengan sendirinya bernilai “manusiawi“, karena ia berada dalam diri manusia itu sendiri. Ajaran agama berada dalam daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
Jadi jelaslah bahwa ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama memang mengisyaratkan adanya intervensi manusia dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Tuhan. Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa bagi setiap orang, agama merupakan hal yang dapat dibedakan dari “paham keagamaan“. Maka, adanya intervensi manusia dalam bangunan keagamaan historis adalah suatu kenyataan.
Adanya lingkungan budaya yang berbeda mengakibatkan munculnya ke-Islaman yang berbeda. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu keuniversalan agama Islam itu sendiri. Hal ini hanya membawa akibat adanya realitas keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama, yaitu keanekaragaman berkenaan dengan tata cara (technicalities), walaupun bisa juga berada dalam tahap keragaman dalam hal yang abstrak dan tinggi, karena itu kebanyakan orang tidak mudah dikenali
22
segi benar atau salahnya secara normatif universal.26 Namun, hal ini tidak ditafsirkan sebagai sebuah sikap untuk mengkompromikan suatu prinsip. Hal ini dimaksudkan bahwa, sebagai “tata cara“, inti persoalan itu semua hanya bernilai “metodologis“ dan “instrumental“, dan tidak bersifat intrinsik atau fundamental.
Jadi, kedatangan Islam itu selalu mengakibatkan adanya perombakan dalam masyarakat atau “pengalihan bentuk“ (transformasi ) sosial kearah yang lebih baik. Kedatangan Islam tidak bersifat “destruktif“ atau bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampaunya semata, melainkan ikut serta dalam melestarikan segala hal yang baik dan benar dari masa lampau dan bisa dipertahankan dengan universalitas Islam. Walaupun dalam kenyataan sosial masih terdapat banyak hal yang belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ajaran agama, karena memang perubahan sosial yang terjadi bersifat evolusionar sehingga membutuhkan waktu yang panjang.
Dalam ilmu falsafah hukum Islam (Ilm Ushul Fiqh) kedudukan sebuah budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan disebut dengan ’Urf. Hal ini harus disadari bahwa adat kebiasaan itu harus dimaknai secara kritis. Bahkan Abdul Wahab Khallaf juga menguraikan bahwa para pembangun mahdzah dahulu juga menggunakan unsur-unsur tradisi sebagai
26 Nurcholis, Islam Doktrin, h. 329.
23
komponen dalam sistem hukum yang mereka kembangkan.
Beliau mengatakan bahwa, ”Oleh karena itulah para ulama berkata: Al’adah Syariah Muhakkamah (adat adalah syariat yang dihukumkan). Dan adat kebiasaan (’urf) itu dalam syara’ harus dipertimbangkan. Imam Malik membangun hukum-hukumnya atas dasar praktik hukum penduduk Madinah, Abu Hanifah dan para pendukungnya beranekaragam dalam hukum-hukum mereka berdasarkan keanekaragaman adat kebiasaan mereka. Imam al Syafi’i setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukumnya karena perubahan adat kebiasaan (dari Irak ke Mesir). Karena itu, ia mempunyai dua pandangan hukum, yang lama dan yang baru (qawl qadim dan qawl jadid). Dalam fiqh Hanafi, banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan yang terkenal, ”al ma’ruf ’urfan ka al masyruth syarthan, wa al tsabit bil ’urf ka al tsabit bi al nash“ (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi dan yang mantap benar dalam kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap dalam nash)“.27
27 ‘Abd al-Waha>b Khalaf, ‘Ilm Ushu>l Fiqh, (Kuwait: al-Da>r al-Kuwaytiyah, 1989), h. 90.
24
E. Tradisi Sedekah Bumi
Ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta dengan apa yang telah dianugerahkan kepada seluruh umat manusia, Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya dan Allah juga yang telah menjaganya, dengan berbagai perubahan musim yang telah mempengaruhi siklus bumi agar seimbang dan berbagai fenomena alam ini kadang manusia tidak dapat menyadari bahwa semua itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu, salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya yaitu dengan melaksanakan ritual upacara sedekah bumi.28
Upacara sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa, sedekah bumi berarti menyedekahi bumi atau niat bersedekah untuk kesejateraan bumi. Bersedekah adalah hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi. Bumi yang hakikatnya sebagai tempat hidup dan bertahan hidup bagi semua makhluk yang ada di dalamnya, sudah selayaknya kita sebagai
28 Joko Darmawan, Mengenal Budaya Nasional “Trah Raja-raja Mataram di Tanah Jawa (Yogyakarta: deepublish, 2017), h. 114.
25
manusia yang sejatinya adalah khalifah29 atau pemimpin di muka bumi ikut menjaga dan mendo’akan agar keselamatan dan kesejahteraannya terjaga. Bila bumi sejahtera, tanah subur, tentram, tidak ada musibah, maka kehidupan di bumi pun akan terjaga dan manusia pun pada akhirnya yang memetik dan menikmati kesejahteraan itu.
Masyarakat Desa Kaplongan Lor sebagian masih peduli dengan pelaksanaan upacara-upacara adat, mereka masih meyakini akan manfaat dari pelaksanaan upacara adat yang sudah terselenggara sejak dahulu, sehingga mereka masih melestarikan upacara-upacara adat. Salah satu upacara adat yang masih dilestarikan adalah upacara adat sedekah bumi.
1. Definisi Sedekah Bumi
Sedekah bumi sebenarnya berasal dari bahasa Arab yakni shodaqoh, dalam kamus bahasa Arab Marbawi kata shodaqoh itu diartikan sebagai pemberian dengan tujuan mendapat pahala (dari Tuhan). Dalam pengertian inilah sedekah yang dimaksudkan secara umum oleh masyarakat Jawa-Islam, yakni pemberian secara sukarela tanpa imbalan apapun sebagai bantuan kepada siapapun, utamanya kepada mereka yang sedang dalam keadaan kekurangan, kesempitan ataupun menderita.30 Akan
29 Munzir Hitami, Revolusi Sejarah Manusia (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 114. 30 Meisil B Wulur, Psikoterapi Islam (Yogyakarta: deepublish, 2015), h. 55.
26
tetapi sebagaimana istilah Arab-arab lainnya, ketika diucapkan dalam lidah Jawa sering menjadi berubah seperti misalnya: Hasan Ali menjadi Kasan Ngali, atau juga Iklas menjadi Iklas atau Eklas, maka demikian juga kata shodaqoh berubah menjadi sedekah. Bahkan ada pula dalam hal-hal tertentu tidak hanya sekedar perubahan atau perbedaan dalam pengucapan, tetapi terdapat perbedaan dalam penerapan dan pemaknaan.
Pengertain harfiyah istilah shodaqoh maupun pengertian yang dipahami dari Al-Qur’an dan Al-Hadits maka yang dimaksud dengan sedekah dalam Islam adalah pemberian bantuan dari sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang dalam keadaan kekurangan.31 Bantuan itu bisa dilakukan dalam bentuk zakat, yaitu amaliyah syariah terstruktur dengan memperhatikan apa yang menjadi syarat dan rukunnya. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat menjadi pemberian yang sifatnya wajib. Sementara di sisi lain pemberian bantuan secara bebas (sunnah) tanpa terikat syariat rukun besar kecilnya niali bantuan yang diberikan. Bantuan semacam ini sering disebut dengan infaq, amal jariyah yang pahalanya seamata-mata dari Allah SWT diyakini akan tetap mengalir jika pemberian itu dilandasi atas niat ikhlas.
Sedangkan sedekah menurut Madchan Anies, sedekah adalah pemberian yang bertujuan untuk
31 Maulana Muhammad Ali, Islamologi: Panduan Lengkap Memamhami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum, dan Syari’at Islam (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah), h. 462.
27
memperoleh pahala dari Allah, sedekah yang hukumnya wajib disebut zakat. Secara istilah infak meliputi nafkah wajib, misalnya zakat, nafkah kepada istri, dan juga meliputi sedekah sunnah. 32
Dalam kamus besar bahasa Indonesia sedekah bumi adalah acara yang dilakukan setelah acara panen padi, tetapi menurut tokoh masyarakat di desa sedekah bumi adalah acara untuk mengucapkan syukur melimpahnya hasi panen di desa dan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan meminta kesuburan tanah dan garapan para petani, selain itu juga ada yang bilang dalam acara sedekah bumi untuk selamatan bumi atau tanah karena semua yang ada di dunia ini berpijak pada bumi atau tanah, sehingga dengan senang hati untuk menyelamati bumi dengan ruwat bumi karena telah memberikan kesuburan tanah bagi para warga. Dengan setiap tahun melakukan sedekah bumi bisa menjaga kelestarian budaya kepada cucu mereka, karena dalam acara sedekah bumi diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa, bagi para pemuda acara ini sangat penting karena bisa menanamkan rasa cinta terhadap alam dan bisa menjaga alam agar tidak rusak dan bisa dinikmati anak cucu mereka.
Upacara sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa,
32 H.M. Madchin Anies, Tradisi Santri dan Kiai (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 17.
28
sedekah bumi berarti menyedekahi bumi atau niat bersedekah untuk kesejahteraan bumi. 33
Selain sebagai acara tahunan, sedekah bumi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepasa Tuhan yang telah memberikan hasil panen yang melimpah. Selain sebagai bentuk syukur, sedekah bumi juga merupakan sebuah do’a supaya diajuhkan dari bala petaka. Dalam melakukan sedekah bumi, masyarakat menyediakan sesaji dari hasil panen mereka. Bentuk sesaji yang diberikan bermacam-macam sesuai dengan aturan adat masing-masing Desa atau tempat mereka. Boleh dalam bentuk sayur, buah, atau hewan ternak. Semua hasil panen tersebut biasanya disajikan dalam bentuk tumpeng. Kemudian tumpeng tersebut dibawa ke tempat berkumpulnya masyarakat dalam melaksanakan sedekah bumi baik itu di Masjid, sawah, ataupun balai desa. Tergantung dengan kesepakatan masyarakat setempat, yang kemudian setelah berkumpul tumpeng-tumpeng tersebut dibacakan do’a.
Makna simbolik dibalik sesaji sedekahan dan selametan diantaranya adalah ubarampe (piranti atau hardware dalam bentuk makanan),34 yang disajikan dalam ritual selametan (wilujengan), ruwatan dan 33 Rini Iswari, Pengkajian dan Penulisan Upacara Tradisional di Kabuapten Cilacap (Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2006), h. 58. 34 Mengenai sibmol dalam ritual sedekah bumi baca juga Agus Ali Imron Al Akhyar, Muqoddimah Ngrowo, Tutur Lisan Hingga Tutur Tulisan (Yogyakarta: deepublish, 2015), h. 429.
29
sebagainya. Hal itu merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya pendekatan diri melalui ritual sedekahan, kenduri, selametan, dan sejenisnya tersebut sesungguhnya adalah bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak. Hal itu terkadang juga dimaksudkan sebagai upaya negosiasi spiritual, sehingga segala hal ghaib ayang diyakini berada di atas manusia tidak akan menyentuhnya secara negatif.
Para penganut mistik Jawa dalam muslim Jawa meyakini bahwa berbagai aktivitas yang mempergunakan simbol-simbol ritual serta spiritual tersebut bukanlah suatu tindakan yang mengada-ada dan kurang rasional.35 Sebagian diantara bentuk simbol ritual dan simbol spiritual adalah apa yang disebut dengan seslametan, yang menggunakan sarana tumpeng dengan berbagai jenis umbarampenya. Tumpeng itu sendiri bagi orang Jawa merupakan ungkapan dari metu kang lempeng atau hidup melalui jalan ynag lurus.36
2. Sedekah Bumi di Indonesia
Menurut para ahli sejarah bumi bisa dilacak sejak zaman kuno. Sejak 3000 SM, petani di Jawa telah
35 Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: IKAPI, 2010), h. 52. 36 M. Solikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, h. 49-52.
30
mengenal penanaman padi dengan irigasi,37 selain mereka juga telah mengenal ilmu bintang, perikanan, tenun, batik, gamelan, wayang dan lain-lain. Mereka mengetahui perubahan musim sehingga mereka tahu saat menanam padi. Dalam sistem penanaman padi basah, para petani itu harus menjalin kerjasama yang baik dengan para petani sedesa atau dengan desa tetangga. Saling pengertian dan hormat serta semangat kerjasama demi kebaikan semua pihak telah dipraktikan sejak zaman dahulu, secara logika sudah mengenal prinsip gotong royong diantara penduduk.
Sedekah bumi merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rezeqi dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Bagi masyarakat Jawa khususnya kaum petani dan kaum nelayan,38 tradisi ritual tahunan semacam sedekah bumi bukan hanya merupakan sebagai rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan belaka. Akan tetapi tradisi sedekah bumi mempunyai makan lebih dari itu, upacara 37 Rohany, dkk, Peralatan Produksi Tradisional Perkembangan Daerah Kalimantan Barat (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990), h. 7. 38 (T.p.n.) Persepsi Nelayan Terhadap Usaha Laut (Semarang: Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro, 1999), h. 34.
31
tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari kultur (budaya) Jawa yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian serta kearifan lokal (Local Wisdom) khas bagi masyarakat agraris maupun masyarakat nelayan.39 Karena masyarakat Jawa sendiri memiliki ciri pandangan hidup yakni ralitas yang mengarah pada pembentukan kesatuan antara alam nyata , masyarakat dan alam kodrat yang dianggap keramat. Dan alam merupakan ungkapan kekuasaan yang menentukan kehidupan.40
Sedekah bumi adalah upacara ritual tradisional yang dimana para warga desa menyatakan syukur atas hasil panen yang baik sehingga mereka bisa hidup dengan bahagia mempunyai cukup sandang pangan, hidup selamat dan berkecukupan. Mereka berharap tahun depan dan selanjutnya mereka akan tetap bisa menikmati kehidupan ini bahkan bisa lebih baik. Oleh karena itu sedekah bumi dipandang sangat penting untuk dilaksanakan.41
Sedekah bumi di daerah Cilacap Jawa Tengah, tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dari
39 Aan Hasanah, dkk, Nilai-nilai Karakter Sunda (Yogyakarta: deepublish, 2012), h. 47. 40 Sugeng Pujileksono, Petualangan Antropologi (Malang: UMM Press, 2006), h. 116 41 Suryo S. Negoro, Upacara Tradisional dan Ritual Jawa (Surakarta: Buana Jawa, 2001), h. 43.
32
nenek moyang orang Jawa terdahulu.42 Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani, juga sebagai nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rezeqi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi.
Prosesi acara sedekah bumi ini sendiri dimulai dari Pendopo Wijayakusuma Cakti Kabupaten Cilacap menuju Pantai Teluk Penyu. Ribuan masyarakat ikut serta dalam ritual ini. Arak-arakan kirab yang ini juga dimeriahkan oleh kelompok nelayan seperti: kelompok nelayan Donan, kelompok nelayan Kemiren, dan kelompok nelayan Tegalkamulyan.
Tujuannya sama, yakni untuk mengungkapkan rasa syukur, biasanya dipuncak ada pagelaran wayang kulit. Kalau wayang kulit berhubungan dengan ruwat,43 dan tenongan itu biasanya untuk kenduri atau sekarang semuanya ditambah dengan tahlilan.
Berbeda dengan ritual tradisi sedekah bumi yang ada Sumatera Selatan,44 tepatnya di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin (Muba). Acara sedekah bumi juga dilaksanakn setiap tahun, bahkan aparat dari Kabupaten ikut serta dalam acara ini. Acara ini dari sedekah bumi ini hanya ziarah 42 T.p.n, Petunjuk Wisata Budaya Jawa Tengah (Jawa Tengah: Proyek Sasana Budaya, Direktorat jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), 99. 43 Edi Dimyati, Wisata Kota Tua Jakarta: Panduan Sang Petualang (Jakarta: PT. Gramedia, T.p.t), h. 178. 44 Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat (T.p.n: 1978), h. 222.
33
ke makam nenek moyang dan makan-makan. Makanan khas yaitu lemang (terbuat dari ketan) menjadi makanan utama dalam acara ini. Bagi masyarakat setempat acara sedekah bumi ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sebab selain unik, juga sarat dengan pelajaran agar manusia khususnya umat Islam senantiasa mensyukuri rezeqi yang diberikan oleh Allah SWT.
Lain juga dengan acara sedekah bumi di Bengkulu, justru terlaksananya sedekah bumi karena sudah pernah mendapatkan musibah bagi masyarakat Desa Sumber Urip, Rejanglebong, Bengkulu pada 7 tahun yang lalu. Ketika itu digelarlah acara sedekah bumi dengan tujuan meminta keselamatan, rezeqi dan jauh dari mara bahaya kepada Yang Maha Esa.
Ritual itu dilaksanakan di dua mata air yang terletak di kaki Bukit Kaba, diawali dengan sholat berjamaah kemudian membaca surat Yasin, Tahlil, dan diakhiri dengan do’a. Makan-makan tentu disediakan oleh para masyarakat di Desa itu sendiri, uniknya makanan yang disediakan didapat dari iuran setiap rumah dengan nominal Rp.35.000. masyarakat Desa juga percaya, jika ada yang tidak memberkan sumbangan maka suatu ketika akan tertimpa malapetaka terhadap keluarganya.
Inti acara sedekah bumi ini adalah pertunjukkan wayang kulit yang dilaksanakan sesmalam suntuk pada malam Jumat Kliwon. Dalangnya yang dipercaya warga Desa, tujuannya agar membawa ketentraman.
34
Tentu tidak hanya pertunjukkan wayang kulit bisa, dalam pertunjukkan ini dikhususkan untuk kesadaran masyarakat dalam pentingnya bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan dari bumi yang melimpah ini.45 Pesan itulah yang disampaikan oleh dalang wayang kulit kepada masyarakat.
Masyarakat Dusun Tohe, Desa Uwoe, Muara uya, Tabalong juga melaksanakan tradisi sedekah bumi.46 Kebanyakan mereka berasal dari Jawa, yang transmigrasi ke Kalimantan Selatan. Acara sedekah bumi biasanya dilaksanakan diantara bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Acara sedekah bumi awalnya biasa saja karena pada waktu itu masih merintis dalam pertanian. Tapi setelah bertahun-tahun bercocok tanam hasil dari pertanian terlihat ada kenaikan secara kualitas.
45 Ayatrohaedi, dkk, Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), h. 57. . J. Melalatoa, Sistem Budaya Indonesia (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dengan Penerbit PT. Pamator, 1997), h. 239.
35
BAB III
SEDEKAH BUMI DI DESA KAPLONGAN LOR
A. Gambaran Lokasi Penelitian
Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Cirebon di Tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di Barat. Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 Desa dan Kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Indramayu, yang berada di pesisir Laut Jawa.47
Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni salah satu jalur yang terdapat di Pulau Jawa, terutama pada musim mudik. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan stasiun terbesar di Jatibarang. Wilayah Indramayu cukup luas, yaitu 2.040, 11 Km.48 agar pembangunan dapat dirasakan secara merata maka diperlukan aparat pemerintahan yang membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan. Selain aparat pemerintahan, peran aktif masyarakat adalah roda penggerak
47 http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1052 48 Suryana Prawiradisastra, “Permasalahan Abrasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu” Alami, Vol. 8, No. 2, 2003, h. 42.
36
pembangunan. Dengan kinerja aparat pemerintahan yang baik diharapkan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Daerah Indramayu merupakan salah satu daerah yang secara topografi ketinggian wilayahnya berkisar antara 0-18 m di atas permukaan laut dan wilayah dataran rendahnya berkisar antara 0-6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, pekarangan. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya berupa dengan kemiringan antara 0-2 seluas 201.285 ha (96.03%) dari total wilayah. Keadaan ini terpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan tinggi maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air dan bila musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan.49 Posisi kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pantai Pulau Jawa yang membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi berkisar antara 22.9º-30º C.
1. Kondisi Desa Kaplongan Lor
Desa kaplongan Lor dulunya merupakan Desa Sukamanah Kecamatan Karangampel, sedangkan Desa Kaplongan itu sendiri berada di sebelah selatan Desa Sukamanah. kemudian pemekaran pada tahun 2004 yang akhirnya Desa Sukamanah menjadi Desa Kaplongan Lor, sedangkan Desa Kaplongan itu sendiri menjadi Desa Kaplongan Kidul. Jika Desa Kaplongan 49 Estinintyas, W., dkk, “Identifikasi dan Delineasi Wilayah Endemik Kekeringan untuk Pengelolaan Resiko Iklim di Kabupaten Indramayu.” Jurnal Mterologi dan Geofisika, Vol, 13, No. 1, h. 9-20.
37
Lor Kecamatannya Karangampel sedangkan Desa Kaplongan Kidul Kecamatannya Kedokan Bunder.
Karangampel merupakan salah satu Kecamatan di Indramayu dengan memiliki 11 Desa, Desa Kaplongan Lor merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karangampel dengan jumlah RT 11 dan 3 RW. Perbatasan Desa Kaplongan sebelah Barat dengan Desa Kaplongan Kidul, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pura, Bagian Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari, dan bagian Utara berbatasan dengan Desa Dukuh Jeruk. Kaplongan Lor sebuah entitas, bagian dari masyarakat Indramayu yang memiliki ciri khas tersendiri dengan masyarakat di wilayah lain. Wilayahnya yang berada pada daerah pesisir pantai utara Jawa Barat merupakan wilayah dengan keunikannya tersendiri dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Indramayu yang berada pada wilayah Jawa Barat tentu seharusnya lebih kental akan dipengaruhi oleh Budaya Sunda, akan tetapi hal ini tidak terjadi pada kenyataanya. Kabupaten Indramayu tidak menggunakan Bahasa Sunda maupun Bahasa Jawa sepenuhnya, melainkan memakai bahasanya sendiri yakni yang disebut Bahasa Jawa Bagongan50 dan Basan. Bahasa bagongan biasanya dipakai untuk sehari-hari dengan orang sebaya, dan Bahasa Basan
50 Tati Narawati, Wajah Tari Sunda dari Masa ke masa (T.p.t. P4ST UPI, 2003), h. 390.
38
biasanya dipakai ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, maupun orang yang dihormati.51 Bahasa yang dipakai masyarakat Indramayu banyak menyerap Bahasa-bahasa Jawa serta sedikit Bahasa Sunda.52
Masyarakat Indramayu terdiri dari beberapa jenis masyarakat yang berbeda.53 Masyarakat petani, pedagang, nelayan, pertokoan, dan lainnya ialah yang masyarakat yang mewarnai kehidupan masyarakat Indramayu. Hal ini terjadi dikarenakan letak geografis dan keadaan sosial masyarakat.
Berbagai jenis masyarakat tersebut kini mulai masuk dalam arus modernisasi dan globalisasi sebagai sesuatu yang tidak bisa dibendung. Mereka mulai menggunakan teknologi guna membantu pekerjaan mereka baik itu dalam bertani, melaut, berdagang maupun dalam system pendataan dalam birokrasi. Selain itu, mereka juga sudah menggunakan sistem perbankan dalam keseharian mereka walaupun belum meyeluruh.
51 Sri Saadah Soepono, F.X. Tito Adonis, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap tatakrama Daerah Studi Kasus Pada Komuniti Perkotaan di Yogyakarta (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, T.p.t), h. 69-70. 52 Sidik Permana, Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan (Yogyakarta: deepublish, 2016), h. 116. 53 Halwany Michrob, Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten: Suatu Kajian Arsitektural Kota Lama Banten menjelang Abad XVI Sampai dengan Abad XX (Banten: Yayasan Baluwati, 1993), h. 73.
39
Di Indramayu sendiri makam maupun petilasan leluhur tercatat sebanyak 201 tempat. Sedangkan di Desa Kaplongan terdapat 2 makam yang banyak diziarahi, yang pertama yaitu makam Kiai Arsyad, kemudian makam Ki Buyut Merjan.
2. Kondisi Sosial Keagamaan
Dalam masalah keagamaan, bagi masyarakat Desa Kaplongan Lor sebagian besar patuh dan taat pada agama yang mereka anut yaitu Islam. salah satu contoh tradisi berziarah umumnya berhubungan erat dengan unsur kepercayaan atau keagamaan,54 sebab tradisi ini merupakan aktivitas sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan cenderung sulit untuk berubah. Dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi berziarah sangat erat kaitannya dengan mitos dan aktivitas keagamaan.
Sementara itu dikalangan masyarakat Desa Kaplongan Lor khususnya penganut Islam, sebetulnya aktivitas ziarah ke makam keramat dan doktrin tawassul55 masih menimbulkan perdebatan teologis yang belum terselesaikan, antara pihak yang membolehkan (bahkan menyunnahkan) dan pihak yang membidahkan (bahkan mengharamkan). Pihak yang tidak membolehkan ziarah ke tempat-tempat
54 Tugiyono Ks, dkk, Peninggalan Situs dan Bangunan Bercorak Islam di Indonesia (T.p.t. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 180. 55 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Perantara Terkabulnya Doa (Tawassul), (Jakarta: Akbar Media, 2015), h. 195.
40
keramat dan makam keramat, umumnya berasal dari kalangan Islam modernis. Tapi terlepas dari pertentangan teologis tersebut, ziarah ke tempat-tempat keramat dan makam keramat merupakan sebuah realitas sosial yang tidak bisa diabaikan, bahkan merupakan suatu tradisi yang menarik untuk diteliti.56
Ziarah umumnya menilik pada tempatnya, makam yang menjadi tujuan ziarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makam keluarga dan makam keramat. Pada makam keluarga, misalnya makam orang tua, orang yang berziarah umumnya bertujuan untuk mendoakan arwah orang tua yang telah meninggal dunia dan sudah berada di alam kubur, agar mendapat keselamatan atau tempat yang baik di sisi Tuhan. Jadi manfaatnya bukan ditujukan untuk kepentingan orang yang berziarah, melainkan untuk doa dan kebaikan roh orang yang diziarahi.
Dalam hal ini, ziarah ke makam keluarga memiliki makna kultural yang hampir sama dengan halal bi halal pada hari Raya Iedul Fitri,57 yang dalam periode tertentu, misalnya setahun sekali, orang merasa perlu menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi saudara-saudara dan 56 Moh. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), h. 353. 57 Muhammad Sholikhin, di Balik 7 Hari Besar Islam: Sejarah, Makna dan Amaliah Idul Fitri (Yogyakarta: Garudawacha, 2012) , h. 159.
41
tetangganya. Jika halal bi halal adalah silaturahmi kepada orang-orang yang masih hidup, maka ziarah kubur dianggap sebagai bentuk silaturahmi kepada orang-orang yang sudah meninggal.
Bisa dikatakan bahwa orang yang pada waktu hari Raya Idul Fitri atau pada waktu lebaran tidak pulang kampung untuk halal bi halal, maka ia dianggap sudah melupakan leluhurnya atau sudah lupa pada asal-usulnya. Demikian pula orang yang dalam periode tertentu tidak melakukan ziarah, khususnya jika ia memiliki orang tua yang sudah meninggal, akan dianggap anak tidak berbakti kepada orang tuanya.
Sementara itu ziarah ke tempat-tempat keramat atau makam keramat, tampaknya punya tujuan atau motivasi yang beragam bagi masyarakat yang melakukannya. Hal itu mengingat bahwa orang-orang yang berziarah ke makam keramat atau ke tempat-tempat keramat berasal dari berbagai daerah dan kalangan serta status sosial yang beranekaragam. Bahkan untuk makam keramat yang besar, penziarah bisa berasal dari luar daerah yang sangat jauh, ada dari luar pulau, bahkan sampai luar Negara.
Hal di atas disebabkan oleh ada anggapan di kalangan masyarakat, bahwa, di tempat-tempat keramat tersebut bersemayam roh-roh halus para leluhur atau tokoh yang mempunyai kekuatan-
42
kekuatan di atas kemampuan manusia biasa.58 Para leluhur tersebut biasanya adalah orang yang berjasa, mempunyai kharisma dan dimitoskan oleh penduduknya dan bahkan dijadikan sebagai panutan. Pada saat-saat tertentu, di tempat-tempat keramat tersebut, dijadikan sebagai tempat kegiatan ritual keagamaan, misalnya upacara-upacara persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta dan memohon segala petunjuk yang harus dilakukan.
Oleh karena itu tidak heran apabila tempat-tempat keramat yang dianggap tempat bersemayam para leluhur atau tokoh yang berkharisma, umumnya dijadikan sebagai tempat ziarah bagi masyarakat dengan alasan dan maksud tertentu.59
Ziarah atau nyekar60 menjadi fenomena di seluruh lapisan masyarakat Indramayu, khususnya Kaplongan Lor. Fenomena ini seharusnya tidak terjadi pada masyarakat Indramayu dengan mengingat beberapa faktor yang ada dalam realitas masyarakatnya. Modernisasi yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kaplongan Lor menjadikan masyarakatnya lebih rasional. Namun demikian,
58 Abdul Jamil, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 3. 59 Nina Merlina, “Budaya Spiritual pada Masyarakat Indramayu” Patanjala, Vol. 3, No. 3, 2011, h. 490. 60 Asykuri Ibn Chamin, Zakiyuddin Baidhawy Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara Jawa (T.p.t. Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), h. 133.
43
berbagai keadaan tersebut tidak lantas menghilangkan lokalitas yang ada pada masyarakat Kaplongan Lor. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat Kaplongan Lor masih bertahan dan eksis sampai sekarang. Lokalitas itu salah satunya adalah ziarah (nyekar). Ini terlihat di Makam Keramat Ki Merjan, masyarakat meyakini bahwa makam tersebut masih mempunyai kharisma bagi masyarakat sekitar, makam tersebut diyakini orang pertama yang babad alas daerah tersebut.61
Kaplongan Lor mempunyai 3 buah masjid, 20 Mushola, 4 pondok pesantren, 2 SD, 1 MI, 1 MD, 1 SMP, 1 SMU, 1 SMK, 1 puskesmas. Lahan sawah yang ada di Kaplongan Lor 305 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Kaplongan Lor berjumlah 3.712 jiwa.62
3. Kondisi Sosial Budaya Manusia dilahirkan dan dijadikan makhluk
sosial yang tidak lepas dari hak dan tanggung jawab karena kesadaran manusia yang paling membutuhkan. Rata-rata masyarakat Desa Kaplongan Lor masih banyak menyadari dan sadar akan perlakuannya sendiri-sendiri, terutama tingkah laku dan keadaan yang masih berhubungan dengan etik dan norma serta adat yang berlaku walaupun ada masyarakat yang sifatnya berubah dengan adanya tuntutan zaman dan
61 Wawancara Pribadi dengan Bapak Khoerudin, pada tanggal 27 Oktober 2017. 62 Wawancara Pribadi dengan Kuwu Kaplongan Lor, Bapak Tabroni, 28 Oktober 2017.
44
banyak juga dalam artian segalanya masih terbatas, yaitu perkembangan budaya mengikuti zaman.
Bersamaan dengan itu Desa Kaplongan Lor ingin meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung agar dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dengan tetap mempertahankan kodrat, harkat, dan martabat sebagai manusia beriman.63
Desa Kaplongan Lor terus berusaha dalam bidang sosial dan budaya guna meningkatkan pembangunan keluarga serta masyarakat sejahtera sebagai wahana perwujudan nilai-nilai luhur agama dan nilai-nilai luhur bangsa guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.64
Keadaan sosial budaya yang ada di Desa Kaplongan Lor yaitu kebudayaan yang mencoba menggali dari budaya-budaya yang sudah ada secara turun-temurun, seperti ritual sedekah bumi. Hal ini berarti masyarakat Desa Kaplongan Lor masih tetap kuat melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang mereka. Kebudayaan-kebudayaan yang ada mencoba
63 Olaf Schumann, Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 14. 64 Sutaryo, dkk, Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015), h. 218
45
untuk tetap dipertahankan dan tetap eksis sepanjang zaman serta budaya-budaya ini tidak akan punah oleh arus globalisasi yang semakin canggih dan pengaruh budaya-budaya Barat yang bertentangan terhadap kebudayaan bangsa65 pada umumnya dan masyarakat Desa Kaplongan Lor.
Pembinaan umat manusia mestinya tidak hanya mementingkan kemajuan intelektual semata, tetapi diimbangi dengan pembinaan kebathinan atau kerohanian. Kebathinan merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat, khususnya suku Jawa.66 Karenanya kebathinan sering disebut “Kejawen”. Munculnya berbagai macam aliran kebathinan yang demikian banyak jumlahnya, merupakan bentuk partisipasi dalam memperkuat jati diri dan kepribadian. Kebathinan adalah sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.
Kejawen memiliki tingkat kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang kepada sesama bukan atas alasan ketakutan akan neraka, melainkan kesadaran bahwa setiap perbuatan baik kepada sesama merupakan sikap adil dan baik pada diri sendiri. Kebaikan kita pada sesama adalah kebutuhan diri kita sendiri. Kebaikan akan berbuah
65 Nur Hidaya, Adi Atmoko, Landasan Sosial Budaya dan Psikologi Pendidikan (Malang: Gunung Samudera, 2014), h. 120. 66 Suwarno Imam S, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa (Depok: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 7.
46
kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan kepada sesama akan kembali untuk diri kita sendiri, bahkan satu kebaikan akan kembali pada diri kita secara berlipat. Demikian juga sebaliknya, setiap kejahatan akan berbuah kejahatan pula. Kita suka mempersulit orang lain, maka dalam urusan-urusan kita akan sering menemukan kesulitan. Kita gemar menolong dan membantu sesama, maka hidup kita akan selalu mendapatkan kemudahan.
B. Prosesi Upacara Sedekah Bumi di Desa
Kaplongan Lor
Hubungan manusia dengan alam melahirkan kepercayaan yang juga dilestarikan. Dalam rangka menjaga keharmonisan hubungan antara individu dengan leluhurnya ataupun dengan alam, masyarakat Jawa mengembangkan tradisi slametan67 maupun ziarah kubur serta ziarah ke tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Hal ini disebabkan dalam pandangan masyarakat Jawa roh yang meninggal itu bersifat abadi.68 Orang yang telah meninggal, arwahnya tetap memiliki daya sakti, yaitu dapat memberi pertolongan pada yang masih hidup sehingga anak cucu yang masih
67 Fajriudin Muttaqin, dkk, Sejarah Pergerakan Nasional (Bandung: Humaniora Utama Press), h. 106. 68 Yustinus Tri Subagya, Menemui Ajal: Etnografi jawa Tentang Kematian (T.p.t. Kepel Press, 2005), h. 87.
47
hidup senantiasa berusaha untuk tetap berhubungan dan memujanya.69
Masyarakat Jawa menganut agama Hindu dan Budha serta kepercayaan asli Jawa sebelum masuknya agama Islam di Jawa. Kedua agama tersebut (Hindu dan Budha) didatangkan untuk keperluan legitimasi kekuasaan raja. Di samping itu, Hindu dan Budha didatangkan untuk keperluan istana guna menyerap pengetahuan tentang teknik membuat candi sekaligus merupakan aktivitas unutk menunjukkan kebesaran keraton, upacara istana, teknik memerintah, dan sebagainya. Pengaruh Hindu Bidha lebih terserap pada kalangan elite dan penguasa daripada kalangan masyarakat umum, yang hidup jauh dari pusat kerajaan. Masyarakat umum lebih banyak melakukan tradisi dari kebudayaan aslinya dan mereka memegang teguh pada adat-istiadat serta kepercayaan lama yang diperoleh dari nenek moyangnya.70
Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam ritual tradisi sedekah bumi adalah pengaruh masyarakat pada kebudayaannya yang mampu mengubah sistem kepercayaan suku Jawa, yang semula mempercayai adanya roh nenek moyang yang menempati suatu tempat sehingga tempat itu dianggap angker, sangat
69 Musni Umberan, Sejarah Kebudayaan Kalimantan (T.t: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995), h. 6. 70 Buchari, Ibrahim. Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia (Terjemahan). (Jakarta: FIS UI, 1983), h. 29
48
berubah atau bertambah kepercayaannya akan adanya dewa-dewa. Sebagai seorang awam yang beragama Islam atau kejawen71 dalam melakukan berbagai aktivitas keagamaan sehari-hari, rata-rata dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di dalam alam pikirannya.
Masyarakat Jawa yakin adanya Allah, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yakin adanya nabi-nabi lain, yakin adanya tokoh-tokoh Islam yang keramat, namun mereka juga yakin adanya dewa-dewa tertentu yang menguasai bagian-bagian dari alam semesta memiliki konsep-konsep tertentu tentang hidup dan kehidupan setelah kematian, yakni adanya makhluk-makhluk halus penjelmaan nenek moyang atau orang yang sudah meninggal, yakin adanya roh-roh penjaga tempat tertentu, kegiatan keagamaan orang Jawa yang menganut agama Jawa juga mengenal sistem upacara.
Bentuk pemujaan terhadap roh nenek moyang adalah salah satu bentuk upacara keagamaan yang dilakukan. Adat untuk mengunjungi makam nenek moyang (nyekar) adalah suatu tindakan yang penting
71 Mengenai Kejawen para peneliti menyepakati bahwa Kejawen adalah suatu kepercayaan tentang pandangan hidup yang diwariskan oleh para leluhur Tanah Jawa. Baca Muhaji Fikriono, Puncak Makrifat Jawa: Pengembaraan Batin Ki Ageng Suryomentaram (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2012), h. 125.
49
dalam agama Jawa.72 Dan segala bentuk upacara atau slametan bumi yang dilakukan selalu menggunakan berbagai jenis sesaji (sesajen, sajen).73 Hal ini juga sangat menonjol dalam beberapa upacara ritual sedekah bumi dengan mempertunjukkan wayang kulit sebagai pelengkap ritual tersebut.74
Tradisi sedekah bumi ini, merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Akan tetapi tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu, upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari kultur (budaya) Jawa yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian serta kearifan lokal, khas bgai masyarakat agraris maupun masyarakat nelayan khususnya yang ada di Pulau Jawa.
1. Persiapan Upacara Sedekah Bumi
Perayaan sedekah bumi telah dilaksanakan secara turun-temurun dan tidak diketahui asal-usul
72 Moehadi, dkk, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 83 73 Amri Marzali, Pola-pola Hubungan Sosial Antar Golongan Etnik di Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 153. 74 Agus Maladi Irianto, Tayub, antara Ritualitas dan Sensualitas: Erotika Petani Jawa Memuja Dewi (Bandung: Laboratorium Seni dan Kebudayaan Lengkong Cilik, 2005), h. 73.
50
serta awal mulai dilaksanakannya. Perayaan ini biasa dilaksanakan penduduk Desa Kaplongan Lor setiap tahun, adapun hari dan tanggal biasanya sesuai keputusan dari tetua masyarakat dan dilaksanakan selama 3 hari 3 malam. Adapun hiburan yang biasa menjadi pelengkap sedekah bumi yang ada di Desa Kaplongan Lor adalah hari pertama Wayang Kulit (malam hari), hari kedua Sandiwara (siang malam), kemudian hari yang ketiga pengajian umum (malam hari).75 Sebelum pelaksanaan acara tersebut, jauh sebelumnya pada malam hari tetua masyarakat mengadakan musyawarah dengan warga yang dianggap cukup ikut andil dalam acara ini supaya berjalan lancar.
1.1 Pembuatan Kerangka Bibit Padi Jauh sebelum ditetapkannya acara ritual
sedekah bumi, warga masyarakat yang sudah ditunjuk oleh kepanitiaan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk membuat kerangka bibit padi yang akan diarak dari tempat yang sudah ditentukan ke balai desa, lalu diantarkan ke pemakaman yang dianggap makam keramat. Adapun kerangka bibit padi itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut bibit padi secara simbolik. Kerangka tersebut dibuat dari batang bambu utnuk pikulannya sepanjang 1 ½ meter, kemudian sebagai pengait bibit padinya
75 Wawancara Pribadi dengan Bapak Mukana, Kaplongan Lor 30 Oktober 2017.
51
terbuat dari bambu utuh yang dibelah menjadi empat belahan akan tetapi belahan tersebut tidak sampai pangkalnya karena bagian pangkalnya dilubangin untuk dikaitkan dengan pikulan. Sedangkan ujung yang sudah terbelah dipasang nampan berukuran kecil sebagai tempat bibit padi yang dimaksud. Jelas ukuran bambu untuk pikulannya lebih kecil daripada bambu yang menjadi tempat padinya. Bambu yang dibelah untuk tempat bibit padi dibuat sebanyak 2 buah untuk ujung dan pangkal pikulan.76
1.2 Hiasan penganten Dewa Wisnu dan Dewi Sri Penganten-pengantenan yang dimaksud
adalah kaum laki-laki dan perempuan yang dirias untuk simbol Dewi Wisnu dan Dewi Sri Pohaci. Dalam hal ini, dandanan yang digunakan tidak seperti penganten pada umumnya. Bagi penganten laki-laki menggunakan celana ¼ kaki dan baju panjang penuh lengan dengan warna hitam, sambil memikul cangkul di bahu kanan, sedangkan penganten perempuan menggunakan kebaya dengan ukuran lengan penuh, untuk bagian bawahnya menggunakan kain selendang batik, dan batasan penggunaannya ¼ kaki.77 Tangan kanan sambil menggendong tempat yang terbuat dari anyaman bambu sebagai tempat
76 Wawancara Pribadi dengan Bapak Mukana. 77 Wawancara Pribadi dengan Bapak Ujro, Kaplongan Lor 29 Oktober 2017.
52
beras (simbol makanan pokok). Baik penganten laki-laki maupun penganten perempuan semua menggunakan penutup kepala ketu (topi yang terbuat dari anyaman bambu dengan design kerucut).
1.3 Penataan Makanan dalam Nampan Penataan nampan makanan dilakukan oleh
para ibu-ibu, nampan yang pertama diisi dengan nasi tumpeng yang dihiasi dengan rebusan sayur-sayuran, kemudian nampan yang kedua diisi dengan panggangan ayam utuh (bakakak) yang dihiasi dengan lauk pauk lainnya seperti telor ayam, tempe bacam, tahu goreng. Kemudian nampan yang lainnya diisi dengan makanan ringan di antaranya: pipis (terbuat dari gilingan tepung beras yang ditengahnya dikasih sisiran pisang) ditaroh di pinggir nampan melingkar dua barisan, kemudian koci (terbuat dari gilingan tepung beras yang di tengahnya diberi parutan kelapa yang sudah diaduk dengan gula Jawa, berbentuk piramida) ditaroh di lingkaran dalam nampan dua baris. Sedangkan bagian tengah nampan diisi dengan kacang tanah yang sudah direbus. Adapun semua pinggiran nampan dikasih hiasan berupa lipatan daun pisang dengan design meruncing.78
78 Wawancara Pribadi dengan Ibu Saenah, Kaplongan Lor 29 Oktober 2017.
53
2. Prosesi Acara Sedekah Bumi
Setelah semua persiapan sudah selesai, kemudian pada hari yang telah ditentukan tersebut, tetua adat dan warga masyarakat membawa semua barang-barang yang dijadikan ritual. Pelaksanaannya sekitar jam 13.00 siang diarak menuju balai desa Kaplongan Lor yang tentunya didoakan oleh tetua masyarakat. Sesampainya di Balai Desa Kaplongan Lor bibit padi yang diarak tadi diserahkan kepada Kuwu Desa Kaplongan Lor dan didoakan kembali oleh tetua masyarakat. Kemudian bibit padi tersebut dibawa kembali oleh masyarakat ke makam yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di makam tersebut semua barang bawaan masyarakat ditaroh di sekitar makam, salah satu warga masyarakat kemudian menaroh sesajen yaitu berupa bawang merah, cabe merah, dan daun salam yang ditusuk seperti sate.
Sesajen tersebut dipasang di empat penjuru makam. Kemudian tidak lupa untuk membakar kemenyan sebagai simbol wewangian, tidak lupa juga penaburan bunga-bunga di makam tersebut. kemudian dilakukan acara tahlilan dan doa bersama yang dipimpin oleh tetua masyarakat. Setelah semuanya selesai, makanan yang dibawa oleh masyarakat dibagikan kembali kepada masyarakat dengan rata.79
79 Wawancara dengan Bapak Ujro, Kaplongan Lor 29 Oktober 2017.
54
3. Penutup Acara Sedekah Bumi Dalam acara penutupan malam hari diadakan
pengajian sebagai penutup dari acara sedekah bumi, sedangkan besok siangnya dilakukan pembersihan lingkungan makam keramat dari sampah-sampah bekas acara hiburan selama tiga hari tiga malam, kemudian tahlil secara bersama-sama dengan masyarakat.
55
BAB IV
ANALISIS MAKNA DAN SIMBOL SEDEKAH BUMI
A. Makna Sedekah Bumi Ferdinand de Saussure mengemukakan konsep
tanda, petanda, dan penanda.80 Meskipun teorinya tergolong ke dalam ranah kajian linguistik, namun yang telah dikonsepsikan oleh de Saussure dapat diaplikasikan untuk memahami fenomena tradisi bumi. Alasan peneliti berpendapat demikian karena dalam tradisi ini memiliki unsur-unsur ritual yang sangat bersifat simbolis. Simbol jika dalam teori de Saussure dikenal dengan istilah signifier atau penanda. Setiap petanda selalu memiliki petanda atau signified. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan petanda adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan makna. Karena sesungguhnya petanda adalah yang tersimpan di balik penanda.
Sedangkan menurut Ahimsa-Putra, simbol adalah sesuatu yang dimaknai atau dengan kata lain sesuatu yang menjadi berarti jika diberi makna.81 Jadi simbol merupakan satu kesatuan dari makna karena tindakan-tindakan yang sifatnya simbolik
80 Ferdinand de Saussure, Course in General Linguisitc, (New York: The Philosophical Library, 1959), h. 66-67. 81 Dwi Ratna N, “Perubahan dan Pergeseran Simbol Di Kota Yogyakarta1945-1949," Jantra, vol II, no. 3, Juni 2007, h. 184.
56
dimaksudkan untuk menyederhanakan sesuatu yang mempunyai makna. Sedangkan makna diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada simbol. Keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu simbol pasti mempunyai makna tertentu. Pemaknaan itu tergantung dari individu masing-masing yang di dalam sebuah interaksi seseorang tidak langsung memberikan respon terhadap tindakan itu tetapi didasari oleh pengertian pada tindakan tersebut karena sebagai makhluk yang memiliki akal individu mampu menilai, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan pengertian yang dimaknai oleh nya sendiri.
Prinsip-prinsip Interaksionisme simbolik menurut Manis dan Meltzer sebagai berikut: 1) Tidak seperti binatang yang lebih rendah, manusia
ditopang oleh kemampuan berfikir. 2) Kemampuan berfikir dibentuk oleh interaksi sosial. 3) Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna
dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berfikir tersebut;
4) Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia;
5) Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut;
6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan
57
mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka, dan selanjutnya memilih;
7) Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat.82
Dalam berinteraksi dan bertindak manusia mempelajari simbol-simbol dan makna dari proses sosialisasi. Simbol-simbol tersebut akan ditafsirkan menurut pemikiran masing-masing, makna dan simbol memberi karakteristik khusus pada tindakan seseorang. Manusia memiliki kemampuan berfikir dan merespon semua yang terkait aspek interaksionisme simbolik yaitu sosialisasi, makna, simbol, diri, interaksi dengan masyarakat. Dalam interaksi tersebut manusia mengembangkan pikirannya dan diekspresikan dalam bentuk perbuatan. Manusia juga mampu menciptakan makna baru dari simbol yang ia lihat dari proses interaksi. Sebagaimana tradisi sedekah bumi di Desa Kaplongan Lor sedekah bumi merupakan salah satu contoh konkrit dari aplikasi fungsi sosial sebagai ritual (agama). Tradisi ini bertujuan agar masyarakat selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.
82 Ritzer George dan Douglas J. G., Teori Sosiologi, Penerjemah Alimandan, (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), h. 392-393.
58
Jika menggunakan pendekatan sosial untuk menganalisisnya maka kita akan menyadari bahwa setiap hal yang sepertinya kurang masuk akal ternyata memiliki fungsi. Demikian pula apabila pelaksanaan upacara sedekah bumi dilakukan di kuburan. Hal tersebut mengandung fungsi pengingat untuk semua masyarakat agar ketika mendapatkan nikmat atau berkah dari Tuhan mereka tidak lantas menjadi sombong atau bahkan lupa bersyukur kepada Tuhan, mengingat bahwa semua itu tidaklah abadi karena nantinya semua manusia akan meniggal juga seperti mereka yang telah meninggal mendahului yang masih hidup menghadap Tuhan.
Dalam pernyataanya Durkheim pernah mengemukakan bahwa adanya agama atau praktik ritual memiliki fungsi integrasi, peningkatan solidaritas bahkan membentuk masyarakat.83 Jika dikaitkan dengan tradisi sedekah bumi maka melalui tradisi tahunan ini telah mampu mengundang atau mengumpulkan satu masyarakat desa menjadi satu. Keseimbangan sosial pun juga dapat tercipta setidaknya dari situasi rukun yang terjalin oleh partisipan tersebut.
Masyarakat Desa Kaplongan Lor yang mayoritas bekerja sebagai petani telah lama menjalankan tradisi ini. Dari keterangan Bapak Mukana selaku masyarakat
83 Mohammad Isfiron, Agama dan Solidaritas Sosial: Studi Terhadap Tradisi Rasulan Masyarakat Gunung Kidul DIY” Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), h. 81.
59
menyatakan bahwa tradisi ini telah ada sejak nenek moyang orang Jawa yang percaya adanya Dewi Sri yaitu Dewi penjaga padi. Masyarakat Desa Kaplongan Lor juga mempercayai adanya Dewi Sri yang menjaga tanaman agar tidak terkena hama padi dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Diadakannya tradisi sedekah bumi juga untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, saling tolong menolong dan saling memberi kepada masyarakat sekitar.84
Acara sedekah bumi ini dikaitkan dengan upacara rasa syukur atas kebaikan Dewi Sri yang dianggap Dewi padi. Dalam mitos Jawa, Dewi Sri dianggap sebagai orang pertama yang menanam padi di Jawa. Tidak menutup kemungkinan bahwa sampai sekarang pada setiap rumah masyarakat hampir selalu ada ruangan khusus yang digunakan untuk meletakkan seikat padi, dan palawija sebagai tanda penghormatan kepada Dewi Sri. Barang-barang itu mereka yakini sebagai simbol agar mereka mendapatkan kemakmuran dan rezeki yang melimpah dalam kehidupan dan pekerjaan. 85
Di dalam tradisi sedekah bumi, selain ada proses pembacaan doa, ada juga di setiap tahapan
84 Wawancara pribadi dengan Mukana, Indramayu, 9 November 2017. 85 Sumintarsih, “Dewi Sri dalam Tradisi Jawa,” Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya, vol. II, no. 3, 2007, h. 136.
60
mempunyai simbol masing-masing yang bisa dilihat dari sesaji yang digunakan. Tradisi sedekah bumi ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, namun dilakukan oleh orang-orang yang mempercayai makna dari tradisi ini sehingga tercipta suatu masyarakat pendukung tradisi sedekah bumi.
Simbol dari tradisi sedekah bumi terdiri dari alat pikulan bibit padi, bibit padi, sesajen, tumpeng, jajanan pasar, pertunjukkan wayang, dan pertunjukkan sandiwara (ketoprak). 1. Alat Pikulan Bibit Padi
Alat pikulan bibit padi yang terbuat dari bambu ini mencerminkan sebagai alat yang terbuat dari hasil bumi untuk memikul hasil bumi juga, di sisi lain masyarakat petani harus saling bahu-membahu dalam mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan melalui bumi yaitu berupa padi, hal itu tercermin dalam bambu sebagai alat pikul. Seberapapun beratnya yang kita pikul diterima karena semua itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan media pengait sekaligus tempat bibit padi menjadi lambang masyarakat dalam menyambut panen dan dibebankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari bambu yang dibelah menjadi empat.
Nampan yang dijadikan sebagai penyangga bibit padi dicerminkan sebagai lapisan masyarakat yang secara keseluruhan menghormati sekaligus menjunjung tinggi hasil panen. Rasa syukur kepada
61
Tuhan Yang Maha Esa melalui hasil bumi yang didapatkan sangat berharga bagi masyarakat untuk keberlangsungan hidup.86
Terkadang bukan hanya ikatan padi yang ada di dalam lumbung, padi yang sudah kering dan dibuang tangkainya yang kemudian dimasukkan ke dalam karung juga disimpan di tempat tersebut, dalam pemikiran orang Jawa tumpukan karung yang berisi gabah (padi) itu dijadikan sebagai tandon (penampungan) nanti suatu saat kemarau melanda masih bisa makan. Dan ada juga juga yang meyakini bahwa di ruangan penyimpanan padi tersebut harus ada padi yang tersisa untuk jadi bibit sehingga ruangan tersebut terpenuhi lagi padi dari hasil panen.
Begitu pula dengan pedaringan (tempat menyimpan beras) bermacam-macam modelnya, ada yang terbuat dari tanah liat dan ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Tempat ini juga tidak boleh kosong dari beras walaupun sebentar, mereka meyakini tempat itu adalah hidup dari kehidupan dalam keluarga.
Padi bagi masyarakat Desa Kaplongan Lor ternyata bukan sembarang tanaman. Ia bukan hanya melebihi tanaman lain, tetapi mempunyai kesejajaran dengan manusia. Seperti halnya manusia, padi dipandang berasal dari alam dewata,
86 Wawancara pribadi dengan Supaenah, Indramayu, 30 September 2017.
62
langit, surga, atau Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, padi dan manusia mempunyai siklus hidup yang sama. Suatu kesamaan, kesejajaran, hubungan erat, dan relasi mistis yang justeru mengantarkan masyarakat kita menyatu dan simbiosis dengan alam. Beras, bagi mereka, tidak dilihat dari sudut ekonomi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan kalori, vitamin, protein, dan sebagainya, melainkan merupakan buah perkawinan ilahi, tanaman firdaus, dan memiliki tenaga misterius yang menguatkan lahir-bathin. Sejumlah masyarakat menyatakan bahwa beras adalah makanan ilahi yang akan menimbulkan kekuatan, keberdayaan, dan mencegah kemalasan. Kulitnya tidak akan lapuk, tidak menjadi kotor, dan bulir-bulirnya melantunkan musik saat tertiup angin, tanpa harus tersentuh oleh manusia.87
2. Sesajen/Sajen Sesajen/sajen menurut Bahasa adalah
makanan (bunga-bungaan) yang disajikan untuk atau dijamukan kepada makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain
87 Wawancara dengan Bapak Sarijan Desa Kaplongan Lor, 29 September 2017.
63
yang melambangkan maksud dari pada berkomunikasi tersebut.88
Sesajen dalam pengertian secara luas bisa juga disingkat dengan sajen ini adalah istilah atau ungkapan untuk segala sesuatu yang disajikan dan dipersembahkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun ditakuti atau diagungkan, seperti roh-roh halus, para penunggu atau penguasa tempat yang dianggap keramat atau angker, atau para roh yang sudah mati. Sesajen ini bisa berupa makanan, minuman, bunga atau benda-benda lainnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah sesutau yang bernyawa.
Akan tetapi sesajen atau sajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah manusia atasakemurahan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa kehidupan dan mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Karena semuanya sudah ada ketika kita mulai diberi kehidupan, juga menggambarkan lingkungan biotik yang ada dan terkandung di bumi.
Sesajen hanya berwujud segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Utamanya yang berupa pepohonan, buah-buahan, dan sumber makanan yang lainnya. Selain itu, sesajen juga mempunyai
88 Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, Kamus Bahasa Melayu Nusantara (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h. 2337.
64
arti menurut wujud, rupa warna, dan namanya sesuai pengertain yang diketahui oleh orang Jawa zaman dahulu.
Ariyono Suyono mengartikan bahwa sesajen berarti sesajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral disebagian besar masyarakat kita.89 Pada umumnya acara sacral ini dilakukan untuk memburu dan mendapatkan berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memilki kekuatan ghaib yang berasal dari paranormal atau tetuah-tetuah, semacam keris trisula dan sebagainya untuk tujuan bersifat duniawi. Sedangkan waktu-waktu penyajiannya ditentukan pada hari-hari tertentu, termasuk dalam acara sakral seperti pesta pernikahan.
Harapan bagi masyarakat Jawa, cita-cita luhur yang harus diraih selama mengarungi kehidupan adalah memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Cita-cita itu sifatnya mutlak dan melekat hampir disetiap hati nurani orang Jawa. Makanya demi mencapai cita-cita tersebut selama menjalani kehidupan di dunia, orang Jawa selalu berusaha menciptakan suasana selaras, harmoni dan sinergi sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan terasa adem-ayem.
89 Ariyono Suyono, Kamus Antropologi (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1985), h. 358.
65
Pelajaran mengenai kehidupan dapat sagat dipengaruhi oelh pengalaman konsep-konsep keagamaan. Pengalaman dan pandangan orang Jawa bersifat keseluruhan, tidak memisahkan individu daripada lingkungannya, golongannya, zamannya, bahkan dari alam adikodrati.
Secara turun-temurun nenek moyang orang Jawa mengajarkan bahwa bentuk rasa syukur dan terimakasih mesti diikuti dengan tindakan bersedekah kepada sesama makhluk hidup. Ajaran nenek moyang tersebut sampai saat ini masih melekat dan dijalani. Salah satu bentuk nyata ajaran mewujudkan rasa syukur dan terimakasih tersebut adalah menghaturkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada arwah leluhur dengan disertai selametan atau membuat sesaji.90
Apa yang seperti kita ketahui bahwa isi dari sesajen itu berupa hasil bumi seperti makanan, minuman, buah-buahan, atau benda-benda lainnya. Dalam hal ini, ada beberapa hasil bumi yang dijadikan sebagai sesajen dalam ritual sedekah bumi. Diantaranya: cabai merah, bawang merah, dan daun salam. Bahan sesajen itu ditusuk dengan bithing (lidi kelapa) seperti sate. Cabai merah yang ditusuk lebih awal supaya berada di pangkal lidi, kemudian bawang merah, dan yang terakhir daun salam yang dilipat-lipat. Makna cabai merah
90 Wahyana Giri MC, Sajen dan Ritual Orang Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2009), h. 43-44.
66
melambangkan sifat berani, berani berusaha dan berjuang. Sifat berani yang positif akan menuntun seseorang untuk mencapai kehidupan yang makmur dan bahagia, berani dan memiliki kemauan yang keras untuk menghadapi segala resiko kehidupan.91
Sedangkan bawang merah dan daun salam dalam sesajen ini melambangkan tentang makna hidup. Kita harus sadar di mana kita hidup, apa yang dikerjakan selama hidup, dan kemanalah tujuan setelah mati. Selama hidup juga, kita harus mempunyai arti bagi sesama lingkungan, agama, bangsa, dan Negara. Dalam bermasyarakatpun kita harus bisa berbaur dengan siapa saja.
Selain benda-benda tersebut, dalam proses ritual tradisi sedekah bumi di Kecamatan Karangampel, sesajen juga berupa beberapa bunga yang diletakkan di tempat yang berbentuk seperti mangkuk dan terbuat dari janur. Bunga yang digunakan terdiri dari bunga-bunga yang berbeda. Tidak ada ketentuan mengenai berapa macam bunga, yang terpenting adalah bunga-bunga yang disajikan terdiri dari bunga-bunga yang berbeda. Menurut masyarakat Kecamatan Karangampel, makna menggunakan bunga sebagai kembang setaman untuk siraman Dewi Sri.92
91 Wawancara Pribadi dengan Bapak Mukana, Indramayu, 28 September 2017. 92 Wawancara pribadi Jumiatin, Indramayu, 29 September 2017.
67
3. Tumpeng Tumpeng bagi orang Jawa merupakan
ungkapan dari metu dalam kang lempeng atau hidup melalui jalan yang lurus.93 Selain itu, tumpeng ini sebagai penanda bahwa hasil panen yang diperoleh terbukti dapat dikonsumsi oleh masyarakat tanpa ada kekurangan apapun. Tumpeng juga dapat diartikan sebagai mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul bersama. Tanpa tumpeng, tidak ada alat pemersatu masyarakat yang paling lekat.
4. Jajanan Pasar Adapun jajanan yang terdapat dalam acara
sedekah bumi ini melambangkan sebagai individu harus bisa menjadi bagian dari pada individu lainnya, artinya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat lainnya. Dalam kehidupan kita tidak mungkin hidup dalam kesendirian, pasti membutuhkan orang lain sebagai teman dalam kehidupan di dunia. Masyarakat dikelilingi para tetuah desa maupun aparat pemerintahan sebagai pengayomnya.
5. Kemenyan Kemenyan dalam tradisi sedekah bumi untuk
mengharumkan ruangan yang membawa ketenangan suasana adalah hal yang baik, sama ditinjau dari sudut adat maupun agama. Arang yang
93 M. Solikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa, (Yogyakarta: IKAPI, 2010), h. 49-52
68
dinyalakan melambangkan elemen berupa api yang berguna bagi kehidupan manusia, dupa kemenyan yang artinya keharuman dan ketentraman juga sembah sujud dan penghantar doa kita kepada Tuhan juga menunjukkan eksistensi udara yang bergerak. Karena Rasulullah SAW menyukai wangi-wangian, baik berupa minyak wangi, bunga-bungaan ataupun pembakaran dupa pada pendupaan.94
6. Penganten-pengantenan Sebagai Simbol Dewa Wisnu dan Dewi Sri
Dewi Sri ternyata tidak hanya berkaitan dengan dari mana (bibit) padi beasal-mula, tetapi juga berpaut dengan kesuburan. Di samping simbol padi, Dewi Sri juga simbol kesuburan tanaman-tanaman yang hingga sekarang ini sangat dikenal oleh masyarakat pedesaan di Nusantara seperti, kelapa, pisang, buah-buahan, ubi-ubian, dan sebangsanya. Dewi Sri juga meneguhkan kepercayaan petani bahwa untuk mencapai produksi tertentu dari seluruh olah pertanian haruslah selalu menghormatinya dengan berbagai cara dan sesaji, baik itu sebagai simbol padi maupun simbol kesuburan.
Dalam hal ini, kesuburan juga memang didambakan oleh penduduk bumi yang tidak hanya dikaitkan dengan jenis tanaman tertentu dan hama
94 SjafiI Hadzani, Seratus Masalah Agama (Kudus: Menara Kudus, 1982), h. 35.
69
pemangsanya, tetapi juga menyangkut curah hujan. Dan dalam konteks ini, kesuburan tidak selalu dipautkan dengan Dewi Sri, meski tetap disimbolisasi perempuan. Berbagai cerita menyatakan bahwa kekeringan yang berkepanjangan di suatu tempat tertentu membuat penderitaan bagi penduduknya sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengatasinya. Nyanyian bersama untuk meminta hujan dari berbagai negeri, bangsa, dan etnis adalah juga mantra-mantra yang dipanjatkan ketika mereka dilanda kekeringan. Misalnya, sebuah pujian berbahasa Arab di kalangan muslim santri: “Rabbana anzil Alaina maan midrara dan seterusnya. Pujian ini sering kita dengar dari berbagai masjid atau mushola di pedesaan Jawa khusunya menjelang shalat berjamaah di saat mereka dilanda kekeringan berkepanjangan. Selain itu, dalam tradisi santri pula, bisa dilakukan shalat bersama di lapangan atau di sawah dengan bacaan dan doa khusus yang dikenal dengan shalat istisqa.
Dalam hal ini, masyarakat menganggap Dewi Sri bukan hanya sebagai simbol padi dan Dewi kesuburan, juga sebagai Dewi tanah. Sebuah pandangan yang sangat umum terjadi di banyak suku bangsa. Ini menjadi sangat mungkin dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, karena sejatinya dalam tradisi petani, perempuanlah yang melakukan penanaman,
70
penyiangan, pemanenan, hingga penyiapan menjadi makanan untuk hidup. Laki-laki di sini tugasnya adalah membajak tanah supaya gembur saat ditanam padi nanti, sekaligus mengairi sawah yang notabenenya sawah sangat membutuhkan air yang cukup.
Menurut Pigeaud, cerita tertua yang menghubungkan Dewi Sri dengan tumbuh-tumbuhan khususnya padi dijumpai di dalam Kitab Tantu Panggelaran yang terdapat pada abad 15-16. Biji-bijian atau tubuh-tumbuhan tersebut tidak berasal dari tubuh Sri, namun dari tembolok burung milik Dewi Sri. Dewi Sri dipercaya menjamin kesuburan dan mengajarkan seni sesajian dan langkah-langkah yang berkaitan dengan pertanian.95
Dapat dikatan bahwa hampir semua masyarakat setempat yang bermatapencaharian petani mengenai cerita tentang tokoh yang dipahami oleh sebagian masyarakat daerah Karangampel secara khusus, masyarakat agraris di negeri ini secara umum, sebagai dewi kesuburan, dewi penjaga sawah, atau dewi padi. Jika masyarakat suku Sunda mengenal Dewi Sri sebagai Ni Pohaci. Sedangkan masyarakat di Kalimantan dikenal dengan Putri Liung Indung Bunga, dan masyarakat di Jawa, Madura, dan Banyumas mengenalnya sebagai Dewi Sri itu sendiri.
95 Sumintarsih, “Dewi Sri,” h. 136-144.
71
Selain Durkheim, Geertz yang seorang peneliti budaya di Jawa juga menganggap bahwa setiap budaya tidak ada yang tidak menarik, apalagi tidak masuk akal. Geertz telah berhasil menelaah dan menarik sebuah teori bahwa tradisi dan ritual dalam masyarakat Jawa khususnya, tidak hanya berfungsi untuk mengingatkan kembali kepada keberadaan Tuhan, namun juga sebagai suatu media penghubung atau jembatan individu manusia terhadap seseuatu yang menurut benak mereka adalah yang bersifat eskatologis.96
Eksistensi tradisi sedekah bumi yang masih ada hingga sekarang membuktikan bahwa masyarakat kecamatan Karangampel masih mempertahankan tradisi sebagai prosesi atau ritual yang dijalankan setelah melewati masa panen. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang mereka yang masih mereka jalankan dan lestariksan hingga penelitian ini berlangsung. Tradisi ini merupakan kearifan lokal masyarakat kecamatan Karangampel. Adapun arti kearifan lokal adalah sebagai berikut:
“Kearifan lokal menurut Tim G. Babcock adalah pengetahuan dan cara berfikir dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang
96 Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Snatri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, Penerjemah Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), h. xii
72
lama. Kearifan berisikan gambaran atau tanggapan masyarakat bersangkutan dengan hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, bagaimana lingkungan berfungsi, bagaimana reaksi alam atas tindakan manusia, serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dan lingkungan alamnya.”97 Tradisi sedekah bumi yang dijalankan
masyarakat Desa Kaplongan Lor merupakan pengetahuan dan cara berpikir masyarakat setempat yang berhubungan dengan alam lingkungan karena tradisi ini berbeda dengan tradisi sedekah bumi di tempat lain. Tradisi sedekah bumi di Desa Kaplongan Lor dilakukan setelah masa panen, sedangkan di tempat lain ada juga yang melaksanakan tradisi sedekah bumi sebelum masa panen.
Proses membiasakan tradisi ini jika dibaca dengan teori milik Peter L. Berger adalah termasuk ke dalam fase objektifikasi. Fase ini adalah fase dimana pelaku tradisi menyosialisasikan ritual dan tradisi secara berulang-ulang dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Masyarakat desa Kaplongan Lor telah mengetahui tradisi yang dijalankan orang tua mereka
97 Sumintarsih dkk., Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura, (Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), h. 5.
73
dan mereka juga dikenalkan tata cara melakukan tradisi sedekah bumi bahkan terlibat langsung di dalam rangkaian tradisi tersebut. Dari proses interaksi dan sosialisasi inilah, seseorang melakukan tindakan melalui proses pemaknaan dari simbol-simbol tradisi yang mereka lihat.
Masyarakat kecamatan ini memiliki kepercayaan bahwa dengan melaksanakan ritual ini, panennya bisa menjadi berkah dan diharapkan untuk panen selanjutnya diberikan hasil yang melimpah dan terhindar dari hama, wereng, tikus, walang sangit, dan lain-lain. Selain itu, mereka harap agar hasil panennyaa awet untuk dikonsumsi. Kepercayaan tersebut membuat masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi sedekah bumi sebagai upaya melestarikan tradissi warisan nenek moyang sekaligus sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan alam.98
Menurut David McClelland, suatu kebudayaan bisa menjadi kearifan lokal apabila ada motivasi dari masyarakat setempat untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut guna mencapai tujuannya. McClelland dalam teorinya The Need for Achievement menyatakan bahwa prestasi. Kebutuhan untuk berprestasi yang dilambangkan dalam teori tersebut adalah salah satu dasar kebutuhan manusia, dan sama dengan motif-motif lainnya, kebutuhan
98 Wawancara Pribadi dengan Bapak Taswan, Kaplongan Lor, 30 Oktober 2017.
74
untuk berprestasi ini adalah hasil dari pengalaman sosial sejak masa kecil.99
B. Sedekah Bumi Sebagai Bentuk Tradisi Islam
Nusantara
Pelaksanaan upacara tradisi sedekah bumi yang diselenggarakan di Desa Kaplongan Lor merupakan usaha masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan alam, manusia menjaga hubungan dengan penguasa alam (hablum minallah) dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). Upacara religi atau agama, yang biasanya dilaksanakan oleh banyak masyarakat pemeluk religi atau agama yang bersangkutan bersama-sama mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. 100 pada zaman dahulu, upacara sedekah bumi merupakan sarana pemujaan kepada nenek moyang dan sekaligus pemujaan kepada Dewi Sri (Dewa kesuburan menurut mitologi agama Hindu) agar masyarakat dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diberi kesuburan, sehingga akan tercipta masyarakat toto tentrem gemah ripah loh jinawi.
99 Ari Budhiarno, “Simbol dan Makna Tradisi Penanaman Padi sebagai Kearifan Lokal Desa Yosomulyo,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 50. 100 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropolgi (Jakarta: UI Press, 1981), h. 67.
75
Kini, hakikat upacara tradisi sedekah bumi adalah usaha bersama masyarakat memohon kepada Allah SWT agar selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari bencana serta selalu diberi kesejahteraan atau akan tercipta baldatun toyyibatun warobbun ghofur. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih ada yang memiliki kepercayaan bahwa nasi hajatan memiliki berkah, sehingga ketika nasi hajatan dibawa pulang akan digunakan sebagai pupuk tanaman dengan harapan tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panenan yang melimpah.
Sikap nguri-nguri budaya terhadap kesenian tradisional harus dimiliki oleh generasi muda sekarang. Salah persepsi terhadap acara tradisi sedekah bumi ini sedikit demi sedikit mulai terkikis, sehingga diharapkan pelaksanaan acara tradisi sedekah bumi sejalan dengan ajaran agama Islam. Secara ekonomis, masyarakat tidak diuntungkan dari pelaksanaan acara tradisi sedekah bumi tersebut.
Usaha masyarakat dalam mempertahankan eksistensi tradisi sedekah bumi yang berasal dari tradisi pra aksara dengan memasukkan unsur ajaran agama Islam, menunjukkan telah terjadi sinkritisme antara tradisi pra sejarah dengan tradisi Islam. Pengajian umum, sandiwara dan wayang kulit menunjukkan tradisi pra Islam dan tradisi Islam.
Dalam acara sedekah bumi di Desa Kaplongan Lor, ada beberapa nilai-nilai yang dapat direkomendasikan sebagai nilai-nilai yang perlu
76
diwariskan kepada generasi penerus, yaitu: satu, sikap religious masyarakat, yang tercermin sikap masyarakat yang selalu ingat kepada Allah SWT, sebab alam dan seluruh isinya adalah ciptaanNYA. Semakin manusia itu dekat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menurunkan karunia dan rahmatNYA yang dapat berupa kesejahteraan dan kedamaian. Kedua, akan selalu ingat kepada jasa-jasa leluhur atau nenek moyang yang telah mendirikan Desa. Sikap ini perlu ditanamkan kepada generasi penerus, sehingga harapan kita, generasi penerus akan memiliki sikap mikul duwur mendem jero. Disamping itu, ada beberapa sikap yang telah diperlihatkan oleh masyarakat dalam melaksanakan acara tradisi sedekah bumi, dan sikap itu tertanam dalam hati para pemuda sebagai generasi penerus.
C. Tahlil
Ritual yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan karangampeldalam acara sedekah bumi setelah arak-arakan kemudian diadakan tahlil bersama di makam Ki Buyut pande. Nasi tumpeng dan segala macam makanan didoakan bersama yang dipimpin oleh sesepuh Desa, selanjutnya nasi tumpeng dan makanan yang lainnya disantap bersama.
Tahlil dilakukan untuk memohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan dalam bentuk dzikir dan membaca doa bersama. Dzikir sendiri adalah penghubung anatar hamba dengan Tuhan, doa yang
77
dipanjatkan dalam tahlil tentunya masyarakat memohon agar diberikan keberkahan, keselamatan dari berbagai macam bahaya, dan semoga hasil panennya diberikan hasil yang bagus. Ucapan syukur atas apa yang masyarakat dapatkan selama ini tercermin ketika mereka khusyuk memanjatkan doa kepada sang pencipta.
Dalam hal ini, tahlil dalam sedekah bumi berarti menyedekahi bumi atau niat bersedekah untuk kesejahteraann bumi. Bersedekah dalam hal ini hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, bersedkah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri dari musibha.
Tahlil yang ada di sedekah bumi di Desa Kaplongan Lor juga sebagai bentuk apresiasi masyarakat, ucapan terimakasih masyarakat karena panen mereka diberikan hasil yang bagus. Maka dari itu mereka ingin menyedekahkan sebagian beras mereka dengan membuat nasi tumpeng atau nasi putih biasa yang diberi lauk pauk dalam acara sedekah bumi.
Acara sedekah bumi pada dasarnya sebagai simbol untuk mengucapkan rasa syukur terhadap sang pencipta, meskipun rasa syukur tidak harus dengan diadakannya sedekah bumi. Bisa saja dengan kita lebih tekun beribadah sholat lima waktu tepat waktu, masyarakat menganggap upacara sedekah bumi ini
78
sebagai acara yang sakral yang harus dilakukan setiap tahunnya.
Rasa syukur yang dikemas dengan acara sedekah bumi juga banyak nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya, salah satunya sebagai tempat silaturahmi dan berkumpulnya masyarakat, tidak setiap waktu bahkan diri kita mampu untuk berinteraksi terhadap seluruh warga desa. Baik karena kesibukan ataupun karena keterbatasan waktu dan tempat. Melalui acara sedekah bumi ini menjadi ajang silaturahmi, berbagi cerita dan pengalaman serta dapat menambah harmonisasi tatanan hidup kehidupan masyarakat Desa Kaplongan Lor.
Acara sedekah bumi di Desa Kaplongan Lor selain tahlil juga menjadi ajang interaksi sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong-royong dalam menyelesaikan segala pekerjaan. Masyarakat Kecamatan karangampeljuga terkenal dengan sikap ramah, kekeluargaan dan gotong-royong di dalam kehidupan sehari-hari, itu semua karena Indramayu menjadi bagian dari Pulau Jawa yang bagian Barat. Salah satu kegiatan gotong-royong yang sering dilakukan terdapat dalam masyarakat pedesaan. Mereka biasanya bergotong-royong dengan mengerahkan tenaga tambahan dalam segala aspek
79
kehidupan, terutama dalam pekerjaan bercocok tanam yang masih dilakukan secara tradisional.
Sifat gotong-royong bisa juga disebut dengan tolong-menollong yang merupakan ciri-ciri kehidupan sosial bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup sendirian tetapi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan gotong-royong itu secara jelas tercermin dalam seluruh rangkaian upacara sedekah bumi, bentuk dari gotong-royong dalam upacara sedekah bumi dapat dilihat pada seluruh rangkaian upacaranya.
Seluruh masyarakat terlihat membaur tanpa ada sekat pembeda status sosial mulai dari yang kecil, menengah, hingga kalangan atas dalam acara sedeekah bumi ini. Harapan masyarakat Kecamatan karangampelyaitu menyukseskan acara sedekah bumi ini.
Melihat kenyataan sekarang ini ukhuwah atau persaudaraan itu sangat penting. Di tengah-tengah gejolak modernisasi yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan pribadi untuk diutamakan dan meninggalkan kepentingan-kepentingan umum atau masyarakat. Sehingga dengan selalu melestarikan tradisi sedekah bumi ini akan menepis dan menghilangkan sifat-sifat egois pribadi. Semuanya bersifat terbuka dan umum untuk kepentingan masyarakat demi persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah.
80
Persatuan umat pada masa sekarang ini adalahbagian dari kewajiban yang harus ditunaikan, terlebih dunia Islam sedang menghadapi ujian dan cobaan yang berat untuk diselesaikan secara bersama dalam kerangka persatuan. Ada ciri khas yang menonjol dari umat Islam. Mereka adalah umat tauhid dan satu kesatuan. Dilihat dari konteks tradisi sedekah bumi, persatuan umat sangatlah menyatu dengan tradisi ini. Karena dengan adanya tradisi sedekah bumi sikap persaudaraan Islam terjalin dengan bentuk silaturahmi.
D. Kenduri
Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius. Segala aktifitas dipenuhi dengan serangkain ritual upacara adat. Salah satunya adalah kendurian. Kenduri atau selamatan merupakan suatu upacara yang pokok yang menjadi unsur terpenting hampir disemua ritual atau upacara dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya.101 Termasuk di dalamnya pada
101 Oleh Koentjaraningrat disebutkan bahwa tradisi keagamaan masyarakat Jawa banyak jumlahnya, termasuk di dalamnya kenduri yang juga diklasifikasikan kedalam macam-macam upacara, seperti Kenduri dalam lingkaran hiidup seseorang, kenduri yang berhubungan dengan bersih desa dan pertanian, kenduri yang berhubungan dengan sehari-hari serta bulan-ulan besar Islam, dan kenduri pada saat selo yang diselenggarakan pada waktu yang tidak tetap, berkenaan dengan kejadian-kejadian yang dianggap luar biasa. Selengkapnya lihat, Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 348 atau Cliffor Geertz, Abangan, Santri dan Priyayi dalam masyarakat Jawa, ter. Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), h. 38.
81
saat upacara sedekah bumi. Kenduri merupakan serangkaian dari acara dalam tradisi sedekah bumi yang sampai saat ini dilestarikan oleh masyarakat di Desa Kaplongan Lor.
Pelaksanaan kenduri dalam sedekah bumi ini tidak terlepas dari membuat sesaji yang penuh dengan makna dan simbolik keagamaan. Diantaranya yang wajib ada dalam kenduri adalah: tumpeng, pisang, apem, ayam, serundeng, peyek teri, kembang telon, bubur, jadah sebanyak tujuh warna, bola-bola nasi (golong), pala pendem, kelapa gading, dan nasi wuduk.102 Makna simbolik dibalik sesaji dalam kenduri (selametan) tersebut diantaranya adalah ubarampe (piranti atau hardware dalam bentuk makanan). Hal itu merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagian di antara bentuk simbol ritual dan simbol spiritual adalah apa yang disebut sebagai selamatan, yang menggunakan sarana tumpeng dengan berbagai jenis umbarampenya.
Pada dasarnya wujud tradisi kenduri penuh dengan unsur-unsur kepercayaan Animisme dan Dinamisme, kemudian ditambahi dengan unsur-unsur
102 Moertjipto, dkk, Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek pengakajian dan pembinaan nilai nilai budaya daerah Istimewa Yogyakarta, 1996/1997), h. 97
82
Hindu-Budha serta Islam. Setiap penambahan unsur dalam kenduri tentunya akan mengubah sebuah bentuk kenduri, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tentulah mengalami perubahan. Sebuah pembaharuan tentu berakibat pada perubahan pola kehidupan manusia.103 Keinginan untuk berinovasi membuat manusia meninggalkan tradisi lama untuk menciptakan tradisi baru.
Kegiatan kenduri tetap masih ada, hanya saja bentuknya yang berubah karena nilai-nilai kejawenan sedikit demi sedikit memudar tergeser oleh pengilhaman ajaran Islam yang semakin kuat. Fungsi kenduri yang dahulunya sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan yang sakral, kini berfungsi lebih sebagai sarana untuk bershadaqah serta menjaga hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat. Di Desa Kaplongan Lor acara ritual tingkeban telah lazim berbentuk tidak lebih dari sebuah acara berdoa bersama dalam sebuah pengajian, yang nantinya dilanjutkan dengan makan bersama.
Jika pada zaman dulu acara kenduri dilaksanakan dengan penuh hikmat dan mengikuti kebiasaan menghidangkan sesajian seperti yang 103 Sebuah perubahan sosial selalu berkaitan dengan perubahan budaya. Perubahan sosial (social change) dan perubahan kebudayaan (cultural change) hanya dapat dipisahkan secara teori saja, namun dalam kenyataan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang tidak mengahasilkan kebudayaan. Lihat, Koentjaraningrat, Pengantar ilmu Antropologi, (Jakarta: Aneka cipta, 1990), h. 14
83
disebutkan di atas, maka berbeda dengan yang terjadi pada saat ini. Pada zaman modern, banyak orang yang tidak lagi menghiraukan makna yang terkandung dari sesaji-sesaji yang harus disediakan. Beberapa masyarakat di Desa Kaplongan Lor demi manfaat praktis mengganti makananan-makananan yang penuh makna tersebut bahan makanan mentah (sembako). Tradisi dengan sasaji saat ini hanyalah lebih pada sekedar melestarikan budaya Jawa yang telah ada sejak lama, karena kebanyakan orang yang masih melakukan kenduri tidak tahu arti atau makna sesaji dan prosesi yang dilakukan.
Secara garis besar alasan masyarakat di Desa Kaplongan Lor memilih meninggalkan model kenduri bentuk kuno dan beralih pada bentuk modern antara lain adalah: 1. Praktis, Masyarakat perkotaan merupakan
masyarakat terbiasa hidup dengan cara-cara yang cepat, mudah, serta semuanya serba praktis.
2. Pengoptimalan daya guna 3. Keterbatasan fasilitas 4. Tidak adanya orang tua sebagai pengarah 5. Kesadaran akan agama 6. Penghematan biaya operasional.
Suatu perubahan pasti akan berakibat postif maupun negatif. Termasuk kebiasaaan atau adat dalam melakukan kenduri. Berubahnya bentuk kenduri dari bentuk lama yang sarat akan unsur kepercayaan lama menjadi bentuk baru yang lebih
84
diutamakan unsur Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Islam dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitasnya. Dampak negatif dari terbentuknya adat baru dalam ritual kenduri adalah kenduri tidak lagi sesuai dengan tujuan utamanya yakni beribadah memohon keselamatan dan bershadaqah.
E. Ziarah
Dari segi umum yang paling mencolok dari subsistem kebudayaan batiniah masyarakat Jawa pra Islam adalah keterlibatan terus-menerus orang yang telah meniggal dunia dalam urusan-urusan mereka yang masih hidup, wabah penyakit, malapetaka dan gagal panen dianggap sebagai akibat dari kejengkelan arwah leluhur yang tidak dihormati dengan upacara-upacara semestinya, atau sebagai akibat gangguan para arwah penasaran atau tidak bahagian, yang mungkin hanya bisa dilawan dengan perlindungan roh leluhur yang baik atau bahagia. Ekspresi ritual dari keyakinan ini merupakan inti dari semua upacara-upacara keagamaan yang diselenggarakan secara rumit bagi orang yang telah meninggal dunia mendoakan arwah leluhur pada setiap ritus peralihan atau pada upacara pertanian di pedesaan atau laut.
Dalam masyarakat Kecamatan karangampelberikutnya adalah dengan slametan. Tradisi ini tidak hanya memiliki simbol yang berdiri sendiri, tetapi ada sistem yang mendasari pelaksanaan
85
upacara itu. Dalam menghormati arwah leluhur. Simbol itu memiliki makna yang memungkinkan untuk dipresentasikan menjadi tindakan-tindakan serta terdapat makna bagi para pelakunya. Dalam upacara sedekah bumi ada seperangkat simbol seperti kemenyan, kembang, tumpeng, jajanan, dan bumbu masak yang semua itu tidak berdiri sendiri, tetapi berhimpitan dengan keyakinan pelaku-pelakunya, berdasarkan pedomannya. Pedoman itu dipahami melalui pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, kemenyan yang dikaitkan dengan doa untuk arwah para leluhur, ternyata karena doa dan bau kemenyan akan sampai kepada arwah para leluhur.
Tidak menutup kemugnkinan perkembangan kebudayaan akan terus berlangsung dalam peralihan. Upacara membahagiakan orang yang telah meninggal dunia pra Islam dan bahkan ketika dominasi perdagangan orang muslim telah hadir, nampaknya masih menyisakan tradisi lama terutama di daerah pedalaman. Hal ini bisa dipahami karena Islam memang berkembang melalui pesisir. Demikian pula munculnya kekuatan Islam dalam skala besar juga datang dari pesisir. Hal ini mudah dimengerti, karena pesisir adalah daerah pertemuan berbagai kebudayaan atau tradisi berbagai bangsa, suku, ras dan agama.
Hal inilah yang menyebabkan orang pesisir bersifat lebih terbuka dalam menerima perubahan. Masyarakat pesisir lebih adaptif dengan berbagai budaya yang datang dari luar, dan tentunya melalui
86
proses panjang akan terjadi berbagai percampuran tradisi dari berbagai belahan dunia lain. Sebaliknya masyarakat pedalaman berwatak lebih tertutup, agraris, dan tidak mudah menerima perubahan. Hal ini diakibatkan oleh kehidupan sebagai kaum agraris, yang tidak sering berhubungan dunia luar sehingga perubahan akan terjadi sangat lambat.
Namun demikian kerumitan upacara pra Islam untuk memperingati orang mati dalam perjalanan menuju alam baka berangsur-angsur digantikan dengan praktik Islam dan proses ini mudah dilihat pada masyarakat Jawa. Perubahan dari kebudayaan atau tradisi lama terjadi karena tidak cocok dengan ajaran Islam, misalnya semua orang Jawa yang memeluk agama Islam akhirnya melakukan khitanan. Mereka menyembah Allah menggantikan para dewa karena Islam menentang keras penyembahan selain Allah SWT. Islam mengharuskan penguburan dilaksanakan secara sederhana dan segera, karena orang meninggal dunia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak berpunya sama seperti ketika dia dilahirkan. Perubahan cepat dalam praktik dalam penguburan dengan diterimanya Islam sebagai agama masyarakat Jawa yang baru tampaknya merupakan salah satu keberhasilan paling mencolok menggantikan upacara pembakaran mayat dari Hindu-Budha.
Kuburan orang Islam relatif sederhana bahkan pada periode awal masuknya Islam sampai Mataram
87
awal. Islam memiliki cara tersendiri yang menjamin arwah orang yang meniggal dunia berada dalam ketenangan, termasuk memohonkan dengan khusuk bagi arwah. Masyarakat Jawa Islam menshalati dan mendoakan dengan membacakan sebagian ayat-ayat al-Quran, selanjutnya diikuti dengan tahlil dan surat Yasin bagi yang meniggal sampai hari ketujuh, pada keempat puluh, keseratus, setahun (mendak sepisan), dua tahun (mendak kapindo), dan seribu (nyewu). Setelah itu semua arwah orang yang meninggal tidak lagi didoakan secara individual pada waktu tertentu (haul), melainkan didoakan ke dalm gabungan arwah orang-orang yang sudah meninggal secara kolektif. Para arwah ini biasanya didoakan secara khusus pada bulan kedelapan kalender komariyah (Syaban) oleh setiap keluarga masing-masing dengan menziarahi kubur.
Semua itu tidaklah lepas dari peran para pendakwah yang lebih kita kenal sebagai Walisongo yang sangat popular di masyarakat Jawa. Sebutan Walisongo merupakan sebuah nama yang sangat terkenal dan mempunyai arti khusus. Karena nama ini dikaitkan untuk menyebut nama para tokoh yang dipandang sebagai penyebar Islam di Jawa.