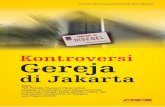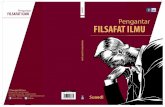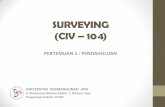Gereja Visi : Gereja yang Peduli dan Berempati Misi : Mewujudkan Jemaat yang Saling Menopang
Sejarah Gereja Indonesia - Peran Bahasa Nasional dan Daerah sebagai Pengantar Injil di Indonesia
Transcript of Sejarah Gereja Indonesia - Peran Bahasa Nasional dan Daerah sebagai Pengantar Injil di Indonesia
SEJARAH GEREJA INDONESIA I
“GEREJA LOKAL DAN ALKITAB BAHASA DAERAH”
(Peran Alkitab Bahasa Daerah dan Nasional Sebagai Pengantar Injil)
OLEH
Kelompok VIII
Hinna K. M. Praing
Grace Balo
Fandrian Kapitan
FAKULTAS TEOLOG
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2014
A. PENDAHULUAN
Masuknya gereja di Indonesia melalui suatu proses perjalanan yang panjang.
Perkembangan gereja di Indonesia mengalami berbagai pergumulan dalam perjalannya itu.
Ada hal-hal yang mendukung namun tidak dipungkiri juga bahwa ada banyak juga hambatan
yang harus dihadapi, dipahami, dan ditangani oleh gereja di Indonesia. Masalah yang cukup
kompleks dan masih dihadapi oleh gereja di Indonesia hingga masa kini adalah konteks lokal.
Dan salah satu isu penting dari konteks lokal tersebut adalah bahasa lokal.
Bahasa adalah bagian penting yang bisa menjadi pendukung sekaligus penghambat.
Apalagi selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia dengan kekayaan
kulturalnya memiliki ribuan bahasa lokal. Jadi, pergumulan penginjilan di Indonesia
berhadapan dengan ribuan konteks lokal yang mana memiliki bahasa pengantar yang
berbeda-beda pula. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat peran bahasa lokal dalam
kaitan dengan mempelajari sejarah gereja di Indonesia, terutama dalam perkembangannya di
daerah.
Dr (HC) Oe. H. Kapita, seorang budayawan dan sejarawan yang dianugerahi gelar Doctor
Honoris Causa dari Virje University, mengatakan bahwa bahwa bahasa lokal memainkan
peranan penting dalam menghantarkan injil masuk dalam hati masyarakat lokal.1 Namun
perlu dicatat pula bahwa ketika injil masuk ke Indonesia, para zendeling dibuat pusing
dengan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Setiap bahasa memiliki rumpun. Dan setiap
rumpun bahasa memiliki dialek.2
B. PERANAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA LOKAL DALAM
PERKEMBANGAN GEREJA DI INDONESIA.
Sejak masuknya gereja ke Indonesia, walaupun dengan ketergantungan pada gereja-gereja di
Indonesia pada Gereja Belanda masih cukup kuat baik secara teologi, daya dan dana, namun
unsur-unsur dan ciri keindonesiaan dan kedaerahan gereja-gereja di Indonesia masih sangat
ditonjolkan. Apalagi ketika Indonesia dalam perjuangan menuju kemerdekaaan, unsur-unsur
yang berbau nasional dan daerah diperkuat untuk menunjukan keberadaan gereja sebagai
bagian dari Indonesia yang merdeka. Semangat gereja-gereja lokal untuk mulai mandiri dan
1 Pidato Oe. H. Kapita, Sumbaas als Voertaal van Christus Evangelie voor de Sumbanzen, disampaikan di
Amsterdam tanggal 21 Oktober 1985. Hlm 1 2 J. S. Aritonang dan Karel Steenbrink, A History of Christianity in Indonesia,Leiden: E.J. Brill, 2008, hlm 145
menjadi sinode-sinode yang independen di masing-masing wilayah pelayanannya mendorong
mereka untuk menonjolkan jati diri keindonesiaan mereka dan terutama kedaerahan mereka.
Salah satu yang paling ditonjolkan dari unsur-unsur nasionalisme dan kedaerahan
adalah bahasa. Kebutuhan akan penguasaan terhadap bahasa nasional dan bahasa daerah
adalah kebutuhan primer dalam penginjilan yang tidak bisa dihindari. Hal ini telah disadari
oleh para zendeling sejak ketika mereka pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia.
1. Bahasa Nasional
Bahasa Indonesia memang telah dipakai secara luas di sebagian besar wilayah
Indonesia terutama pada zaman kolonial Belanda di hampir sebagian besar wilayah
Indonesia sebagai bahasa pengantar terutama sejak sekitar abad ke 17.3 Namun
pertama kali bahasa Indonesia diperkenalkan dan dideklarasikan sebagai bahasa
nasional adalah pada peristiwa momentum tanggal 28 Oktober 1928, yakni Peristiwa
Sumpah Pemuda. Salah satu poin dalam Sumpah Pemuda adalah menyatakan bahwa
bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Dan setelah kemerdekaan, Pasal 35 dan 36
UUD 1945 memperkuatnya sebagai bahasa nasional yang resmi berlaku di seluruh
wilayah Indonesia.4
Bahasa Indonesia pada dasarnya adalah bahasa melayu yang mengalami
modifikasi dan penyerapan-penyerapan kata dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia
(seperti Maluku dan Jawa), bahasa Portugis, bahasa Cina, dan juga bahasa Belanda.
Pengaruh Portugis terhadap bahasa Indonesia mulai terjadi sejak abad ke 16.5
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di wilayah jajahan
Belanda, terutama sejak abad ke 17 adalah untuk kepentingan kerja sama perdagangan
dan juga mempermudah komunikasi di wilayah Indonesia yang begitu kaya akan
ragam bahasa ini. Mereka kesulitan berkomunikasi dengan masyarakat pribumi. Oleh
karena rumpun bahasa yang paling menonjol di wilayah Indonesia adalah bahasa
Indonesia.6 Maka pemerintah Belanda melakukan standarisasi bahasa pada Bahasa
Indonesia dan menjadikannya bahasa pengantar resmi di seluruh wilayah Hindia
Belanda.7
3 Aritonang dan Steenbrink, op.cit. hlm 35
4 http://id.wikipedia.org/bahasa_indonesia diakses pada 25 November 2014.
5 Aritonang dan Steenbrink, op.cit hlm 35
6 Ibid. hlm 126
7 http://id.wikipedia.org/bahasa_indonesia diakses pada 25 November 2014.
Selain dalam dunia perdagangan dan kepentingan kolonialisasi, bahasa
Indonesia pun turut menjadi bahasa pengantar di dalam gereja-gereja dan kegiatan
penginjilan di Indonesia. Sejauh ini bahasa Indonesia cukup berperan terhadap
pekabaran injil di Indonesia. Dengan adanya suatu bahasa nasional yang
mempersatukan Indonesia turut mempermudah pekerjaan gereja di Indonesia.
Tetapi persoalannya adalah selain bahasa nasional ini, ribuan bahasa lokal
lainnya adalah bagian dari keragaman budaya yang tidak bisa tergantikan begitu saja.
Bahasa Indonesia hanya menyentuh kelas masyarakat terdidik saja. Sedangkan
masyarakat kelas bawah masih sangat bergantung dengan bahasa daerah. Sehingga
lagi-lagi bahasa Indonesia belum seratus persen membantu pekerjaan penginjilan di
Indonesia.
Untuk pemerintah ,dalam urusan perdagangan, memang hanya berurusan
dengan kalangan menengah ke atas yang telah mengenyam pendidikan dan menguasai
bahasa Indonesia. Sehingga kesulitan ini tidak begitu terasa. Namun untuk gereja
yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama kelas bawah, ini adalah
persoalan serius karena penginjilan hanya menyentuh mereka yang di kelas atas saja.
2. Bahasa Daerah
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa bahasa Indonesia belum
begitu membantu kegiatan penginjilan. Bagaimanapun juga, setiap daerah memiliki
konteks lokal yang tidak sama satu sama lainnya.8 Sehingga dalam kebutuhan itu,
para misionaris berusaha untuk sedapat mungkin menguasai bahasa lokal demi
memahami konteks lokal. Bahasa lokal sebagai pengantar dalam upaya penginjilan
sangat membantu para penginjil dalam menyentuh masyarakat Indonesia dari
berbagai kalangan dan kelas masyarakat.9
Sekalipun banyak pula golongan penginjil konservatif yang menganggap
bahwa bahasa lokal harus digantikan dengan bahasa Indonesia atau Belanda karena
menganggap bahasa lokal itu seperti bagian dari kekafiran. Namun kenyataannya,
para penginjil ini mengalami kesulitan dalam menjangkau kalangan masyarakat
bawah. Sebagai contohnya adalah Ds. Goosen yang berusaha menghapus seluruh
unsur budaya dari gereja di Sumba. Namun ia justru mengalami penolakan dari
8 Aritonang dan Steenbrink, op.cit, hlm 147
9 Ibid. hlm 146
masyarakat setempat. Hanya sekelompok masyarakat yang setia dengannya yang
membentuk sebuah gereja bernama Gereja Bebas Goosen.
Ini membuktikan bahwa peranan bahasa lokal itu bukanlah hal bisa diabaikan
begitu saja. Para penginjil yang menginjakan kakinya di Indonesia mau tidak mau
harus mempelajari bahasa lokal ketika mereka diperhadapkan pada konteks lokal.
Para penginjil seperti De Bruijn dan Wielenga di Sumba, P. Middlekoop di Timor, A.
C. Kruyt di Poso, mereka cukup sadar akan kebutuhan penginjilan dalam bahasa
lokal.
3. Bahasa Sumba sebagai Pengantar Injil pada orang Sumba
Oe. H. Kapita menjelaskan dalam pidatonya di depan Senat Guru Besar Vrije
University Amsterdam pada tanggal 21 Oktober 1985, bahwa salah satu injil tidak
benar-benar masuk dalam hati orang Sumba pada waktu J. J. van Alpen tiba di Sumba
(sebagai salah satu konteks lokal) adalah karena van Alpen tidak menguasai bahasa
Sumba sebagai bahasa lokal. Sebagai akibatnya, van Alpen justru hanya mampu
berkarya dikalangan orang Sabu dan guru-guru Ambon yang juga mengajar di
kalangan orang Sabu saja.10
Melihat hal itu, Pdt. de Bruijn yang diutus menggantikan Pdt. van Alpen,
sadarh bahwa untuk bisa masuk ke dunia orang Sumba, maka haruslah menguasai
konteks dan budaya orang Sumba. Untuk memahami itu perlulah seorang penginjil
menguasai bahasa Sumba. Sejak itu dimulailah suatu usaha penerjemahan bahan-
bahan penginjilan ke dalam bahasa Sumba dan mempersiapkan para penginjil dari
Belanda dengan kemampuan berbahasa Sumba. Kesuksesan demi kesuksesan mulai
tercapai dalam penginjilan di Sumba. Perintis upaya tersebut yang cukup sukses di
antaranya adalah Pdt. Wielenga.11
Namun bahasa Sumba juga memiliki kelas-kelas dan berbagai tipe dialek. Ada
dialek Sumba Barat (Wewewa) dan dialek Sumba Timur (Kambera). Demikian pula
ada gaya berbahasa tinggi yang biasanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan imam
agama Marapu yakni luluku. Dan gaya berbahasa orang kelas merdeka dan hamba.
Orang yang mampu berbahasa Sumba kelas tinggi, dianggap sebagai orang yang
berkasta tinggi. Orang Sumba yang beragama Marapu percaya bahwa yang Ilahi
berbicara kepada para Imam dengan bahasa Sumba kelas tinggi. Sehingga para
zendeling seperti Pdt. Wielenga lebih memilih untuk mendidik orang-orang Kristen
10
Oe. H. Kapita, op.cit. hlm 5-6 11
Ibid.
keturunan bangsawan dan imam untuk menjadi guru-guru injil yang membantu
Zending untuk mengabarkan injil di kelas bawah. Sebab para penganut agama Marapu
akan menganggap bahwa guru injil pribumi itu memang sedang menyampaikan pesan
Ilahi oleh karena mereka menggunakan bahasa yang sakral.12
Hingga kini Gereja Kristen Sumba masih mempertahankan bentuk-bentuk
bahasa tinggi ini dalam kegiatan kegerejaan. Misalnya dalam upacara penabhisan
pendeta, affirmasi/Sidi, dan pengutusan. Selain itu Alkitab Bahasa Kambera misalnya
juga masih mempertahankan bentuk-bentuk bahasa tinggi dalam tata bahasa Alkitab
itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Oe. H. Kapita bahwa bahasa Sumba adalah
kunci masuk injil ke hati orang Sumba adalah suatu bukti nyata akan peranan bahasa
lokal dalam perkembangan gereja.
C. UPAYA PENERJEMAAHAN ALKITAB
1. Sejarah LAI13
Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) adalah sebuah lembaga yang mengusahakan
alihbahasa Alkitab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, serta
penyebarannya. Lembaga Alkitab Indonesia adalah anggota dari United Bible
Societies, sebuah organisasi yang menaungi ratusan Lembaga Alkitab nasional
yang giat mengerjakan penerjemahan, produksi dan penyebaran Alkitab di seluruh
dunia.
Jauh sebelum berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), pada tanggal 4
Juni 1814 telah didirikan suatu Lembaga Alkitab di Batavia (sekarang Jakarta) di
bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Lembaga
Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris dan
dinamakan Lembaga Alkitab Jawa (Java Auxiliary Bible Society).
Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816,
Lembaga Alkitab ini diganti namanya menjadi Lembaga Alkitab Hindia-Belanda
(Nederlands Oost-Indisch Bijbelgenootschap) atau dikenal dengan sebutan
Lembaga Alkitab Batavia (Bataviaas Bijbelgenootschap).
Pada 1950 bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, beberapa tokoh kristiani mulai
12
F. D. Wellem, Injil dan Marapu, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004, hlm 86-87 13
http://id.wikipedia.org/Lembaga_Alkitab_Indonesia dan http://www.sejarah.co/Sejarah _Alkitab_Indonesia diakses pada 25 November 2014.
memprakarsai berdirinya LAI. Sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan
negara, timbullah keinginan untuk berdikari, bertanggungjawab penuh terhadap
pengadaan serta penyebaran Alkitab.
Pada tanggal 9 Februari 1954 Lembaga Alkitab Indonesia secara resmi
didirikan dengan Akta Notaris nomor 101. Sebelumnya, pada 1952, LAI sudah
diterima sebagai anggota madia (associate member) dari Persekutuan Lembaga-
lembaga Alkitab Sedunia (United Bible Societies) pada persidangannya di
Ootacamund, India dan diterima menjadi anggota penuh (full member) pada
persidangan Persekutuan Lembaga-lembaga Alkitab Sedunia di Eastbourne,
Inggris pada bulan April 1954.
Untuk pertama kali LAI diketuai oleh Dr. Todung Sutan Gunung Mulia,
seorang tokoh Kristen Indonesia yang namanya diabadikan untuk BPK Gunung
Mulia. Kemudian jabatan ketua itu berturut-turut digantikan oleh G.P. Khouw,
S.H., Ph. J. Sigar S.H., Pdt. W.J. Rumambi, Pdt Chr. A. Kiting dan sejak tahun
1989 dipegang Drs. Supardan M.A
2. Upaya Penerjemahan Alkitab
- Dalam Bahasa Indonesia
Pada tahun 1612 telah ada upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa
Melayu yang adalah akar bahasa Indonesia oleh seorang pedagang VOC
bernama Albert C. Ruyl namun itu baru terdiri dari Injil Matius dan Markus.
Sejak tahun 1612 hingga sekarang ini sebenarnya paling sedikit ada sekitar 22
versi terjemahan Alkitab dalam Bahasa Melayu-Indonesia.14
Dari sekian banyak versi terjemahan Alkitab yang telah diterbitkan yang
cukup populer ditelinga kita adalah Alkitab Terjemahan Lama (TL) yang
merupakan gabungan dari terjemahan PL karya Klinkert dan PB karya Bode.
Alkitab TL sebenarnya adalah cetakan Alkitab yang darurat diterbitkan
kembali oleh LAI pada tahun 1958 pasca kemerdekaan Indonesia. Sedangkan
Alkitab Terjemahan Baru (TB) itu baru diterbitkan pada tahun 1974. Dan pada
tahun 2000, LAI mengeluarkan Revisi dari Alkitab TB bagian Perjanjian
Baru.15
14
http://www.sejarah.co/Sejarah_Alkitab_Indonesia diakses pada 25 November 2014 15
Ibid.
- Dalam Bahasa-bahasa Lokal
Upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah di Indonesia
telah dimulai sejak tahun 1820 oleh seorang penginjil asal Jerman yang
bernama Gottlob Bruckner. Alkitab itu adalah PB dalam Bahasa Jawa yang
diselesaikan percetakannya di India pada tahun 1831. Namun karena suatu
masalah yang tidak begitu jelas, pemerintah menyita terjemahan Alkitab itu
dan baru diizinkan untuk disebarkan kembali pada tahun 1848.16
Hingga kini pekerjaan penerjemahan Alkitab terus dilakukan di seluruh
Indonesia. LAI pun tidak bekerja sendiri dalam upaya penerjemahan Alkitab
ke dalam bahasa daerah. Ada pula Lembaga Biblika Indonesia (LBI) yang
berada di bawah naungan Gereja Katolik Roma, ada Lembaga Penerjemaan
Alkitab Wycliffe, serta ada pula Gereja-gereja yang memiliki unit kerja yang
bertugas menterjemahkan Alkitab seperti Unit Bahasa dan Budaya (UBB)
GMIT yang telah berhasil menerbitkan Terjemahan Alkitab dalam bahasa
Kupang, Rote dan beberapa bahasa daerah lainnya di wilayah pelayanan
GMIT. Untuk Sinode GKS ada Lembaga Penerbitan Kristen dan Deputat
Penterjemah Naskah-naskah Gerejani yang bekerja dibawah Dewan Penata
Layanan GKS yang bekerja sama dengan GKN dalam upaya menerbitkan dan
melestarikan naskah-naskah terjemahan ke dalam bahasa Sumba17
.√
Tabel. Timeline Penerjemahan Alkitab ke Bahasa Daerha dari 1820-
197018
Tahun Peristiwa
1820 Bruckner menyelesaikan penterjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa
Jawa.
1829 Terjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jawa oleh Gottlob Bruckner
selesai dicetak di India.
1831 Perjanjian Baru terjemahan Bruckner selesai dicetak, dan disita
pemerintah.
1846 Perjanjian Baru bahasa Dayak-Ngaju dicetak oleh August Hardeland di
Afrika Selatan.
16
Ibid. 17
Oe H .Kapita,op.cit., hlm 16 18
http://www.sejarah.co/Sejarah_Alkitab_Indonesia diakses pada 25 November 2014
1848 Dr. J.C.F. Gericke menyusun terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa
Jawa.
1848 Perjanjian Baru terjemahan Bruckner boleh disebarkan lagi.
1854 Dr. J.C.F. Gericke menyusun terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa
Jawa.
1858 Perjanjian Lama bahasa Dayak-Ngaju dicetak oleh August Hardeland.
1874 L.E. Denninger menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Nias.
1874,1891 Penerjemahan Alkitab Injil Lukas, 1874 dan Perjanjian Baru, 1891 dalam
bahasa Nias dikerjakan oleh H. Sudermann dengan bantuan Ama
Mandranga, dan beberapa orang Nias lainnya.
1877 S. Coolsma menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Sunda.
1885 Dr. L.I. Nommensen menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa
Batak Toba.
1887 Raden Ng. Djojo Soepono bekerjasama dengan P. Jansz dalam hal
penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jawa.
1887 Dr. B.F. Matthes menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa
Makassar dan Bugis.
1890 P. Jansz menterjemahkan ke dalam Perjanjian Baru bahasa Jawa.
1891 S. Coolsma menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Sunda.
1893 P. Jansz menterjemahkan ke dalam Perjanjian Lama bahasa Jawa.
1897 Jansz menyelesaikan terjemahan Perjanjian Lama.
1900 Dr. B.F. Matthes menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa
Makassar dan Bugis.
1906 Jansz menyelesaikan terjemahan Perjanjian Lama.
1913 Terjemahan seluruh Alkitab dalam bahasa Nias selesai dicetak oleh
Sundermann, dkk.
1928 J.H. Neumann menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Karo.
1933 Dr. Adriani menggubah terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Bare?e.
1948 Dr. P. Middlekoop menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Timor
(Perjanjian Baru 1948, Perjanjian Lama tidak terbit).
1950-1959 J.L. Swellengrebel di Jakarta turut mengerjakan terjemahan Alkitab ke
dalam bahasa Bali dan bahasa Indonesia.
1951,1960 H. van der Veen menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Toraja
(Perjanjian Baru 1951, Perjanjian Lama 1960).
1953 J.H. Neumann menerjemahkan sebagian besar Perjanjian Lama ke dalam
bahasa Karo.
1961 Perjanjian Baru dalam bahasa Kambera (Sumba Timur) diterbitkan oleh
Alkitab Indonesia.
1970 Perjanjian Baru dalam bahasa Wewewa (Sumba Barat) diterbitkan oleh
Alkitab Indonesia.
3. Upaya Penerjemahan Alkitab ke Dalam Bahasa Sumba Sebagai Salah Satu
Bahasa Lokal
Sekalipun Alkitab dalam Bahasa Sumba baru diterbitkan oleh LAI pada tahun
1961 dan 1970, namun sebenarnya upaya penerjemahan dan pelestarian Alkitab
ke dalam bahasa Sumba sudah dimulai sejak 1890 dan dirintis dan diupayakan
oleh J. de Roo van Alderwerelt, Pater J. H. van der Velden, Pdt. W. Pos, Prof. J.
C. G. Jongker, dan Pdt. Wielenga. Upaya mereka mendapat dukungan penuh dari
Nederlands Bijbelgenootsschap (Lembaga Alkitab Belanda). Selain
menterjemahkan Alkitab, mereka juga menerjemahkan naskah-naskah penting
seperti Katekismus Hiedelberg.19
Pdt. Wielenga pada tahun 1909 berhasil menyelesaikan dan menerbitkan buku
“Schet van den Sumbaneesche Spraankunst” dan “Sumbaneesche Woordenlijst”
yakni suatu Tata Bahasa Sumba dan Kamus Bahasa Sumba dalam bahasa Sumba
dialek Kambera. Karyanya ini sangat membantu para zendeling dalam belajar
bahasa Sumba.20
Khusus untuk penerjemahan Alkitab, dapat dikatakan bahwa dalam
penerjemahan Alkitab dalam Bahasa Sumba, seorang ahli bahasa Sumba bernama
Dr. L. Onvlee lah yang mengambil peran yang cukup penting. Ia berhasil
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Kambera dan Wewewa, walaupun
belum lengkap sebab masih ada bagian yang belum diselesaikannya. Namun
pekerjaan itu sudah sangat membantu dan disempurnakan oleh Deputat
Penerjemahan Naskah-naskah Gerejani GKS dan diterbitkan oleh LAI tahun
1970.21
19
Oe. H. Kapita, op.cit. hlm 12 20
ibid 21
F.D. Wellem, op.cit, hlm 86 dan Oe. H. Kapita, op.cit. hlm 16