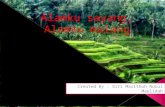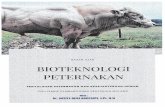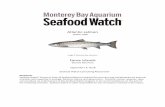REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH SKRIPSI
Transcript of REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH SKRIPSI
REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat
Utama Sosiologi Pembangunan
Oleh:
Gadi Kurniawan Makitan
NIM. 0710010009
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2011
i
REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH
SKRIPSI
Disusun oleh:
Gadi Kurniawan Makitan
NIM. 0710010009
Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan:
Pembimbing pendamping
Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.
NIP. 19530708 197903 2 001
Tanggal : 18 Agustus 2011
Pembimbing utama
Dr. Mardiyono Djakfar, MPA
NIP.19520523 197903 1 001
Tanggal : 18 Agustus 2011
ii
REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH
SKRIPSI
Disusun oleh:
Gadi Kurniawan Makitan
NIM. 0710010009
Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana pada tanggal
25 Agustus 2011
Tim Penguji:
Pembimbing utama
Dr. Mardiyono Djakfar, MPA
NIP.19520523 197903 1 001
Tanggal : ...............................
Pembimbing pendamping
Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.
NIP. 19530708 197903 2 001
Tanggal : ...............................
Anggota Penguji 1
Nike Kusumawanti, MA
NIP. -
Anggota Penguji 2
Haris El Mahdi, M.Si.
NIP. -
Malang, 25 Agutus 2011
Dekan,
Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, MS
NIP.19561227 198312 1 001
iii
PERNYATAAN
Nama: Gadi Kurniawan Makitan NIM: 0710010009
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.
Malang, Agustus 2011 Yang membuat pernyataan
Gadi Kurniawan Makitan NIM. 0710010009
iv
Riwayat Hidup Gadi Kurniawan Makitan
0710010009 Data Pribadi Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Februari 1989 Alamat : Jl. Kasiman No.1 RT 004/RW 005 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu Kota Batu Alamat e-mail : [email protected]; [email protected] Riwayat Pendidikan 2007-2011 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang 2004-2007 Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Albertus Malang 2001-2004 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batu 1995-2001 Sekolah Dasar Immanuel Batu
Pengalaman Kerja Oktober-November 2010 Praktek Kerja Nyata di Malang Corruption Watch November 2010-... Badan Pekerja Malang Corruption Watch Pengalaman Organisasi 2011-... Pengurus Brawijaya Sociological Thought 2009-2010 Ketua Panitia Kamp KTB Perkantas Malang 2009-2010 Ketua Tim Pembimbing Siswa Perkantas Malang 2007-2009 Koordinator Tim KTB, Tim Pembimbing Siswa Perkantas Malang
i
KATA PENGANTAR
Penulis bersyukur karena skripsi yang berjudul “REPRODUKSI BUDAYA POLITIK MALANG CORRUPTION WATCH” ini bisa selesai. Ini semua dimungkinkan karena Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berkarya.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.
Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak sehingga penulis perlu mengucapkan terimakasih kepada mereka yang disebut di bawah ini:
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Darsono Wisadirana, MS; selaku Dekan FISIP dan Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si.; selaku ketua jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mardiyono Djakfar, MPA; Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si., dan Bapak Anton Novenanto, MA, selaku pemimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini, yang juga memberi pencerahan dan dorongan untuk maju.
3. Ibu Nike Kusumawanti, MA dan Bapak Haris El Mahdi, M.Si.; selaku penguji yang telah membuat naskah awal penulis menjadi lebih baik
4. Rekan-rekan Malang Corruption Watch, yang disadari atau tidak telah membantu banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Orang tua penulis, yang tidak pernah setengah hati mendukung penulis dalam berkarya.
6. Keluarga Rupat (Ita, Tanti, Tante Heri, Mbah Mi, Dhe Mul), yang selalu menjadi “rumah” bagi penulis.
7. Tery, yang tidak pernah lelah berdoa, memberi semangat, dorongan, dan perhatian; yang selalu menjadi teman dalam masa-masa sulit.
8. Teman-teman seperjuangan penulis, yang bersedia menjadi teman diskusi, berbagi informasi, maupun berbincang santai di tengah-tengah kepenatan.
. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang menggunakannya.
Malang, Agustus 2011
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................. i
Daftar Isi ......................................................................................................... ii
Daftar Tabel .................................................................................................... iii
Daftar Gambar ............................................................................................... iv
Daftar Lampiran ............................................................................................ v
Abstrak ............................................................................................................ vi
Abtsract ........................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 8
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 9
1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 11
2.1. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 11
2.2. Budaya Politik ..................................................................................... 16
2.3. Civil Society ........................................................................................ 22
2.4. Reproduksi Budaya dan Reproduksi Sosial ........................................ 29
2.5. Alur Berpikir ....................................................................................... 34
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 36
3.1. Jenis Penelitian .................................................................................... 36
3.2. Penetapan Lokasi Penelitian ............................................................... 36
3.3. Fokus Penelitian .................................................................................. 37
3.4. Sumber Data ........................................................................................ 38
3.5. Proses Pengumpulan Data ................................................................... 38
3.6. Keabsahan Data ................................................................................... 41
iii
3.7. Teknik Analisa Data ............................................................................ 42
3.8. Posisi Penulis di Malang Corruption Watch ....................................... 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 49
4.1. Gambaran Umum ................................................................................ 49
4.1.1. Profil Malang Corruption Watch ............................................. 49
4.1.2. Aktor-aktor Malang Corruption Watch .................................... 53
4.1.3. Aktivitas-aktivitas Malang Corruption Watch ......................... 60
4.1.4. Kalimetro: Lokasi Geografis Malang Corruption Watch......... 71
4.2. Domain-domain Budaya yang Ditemukan .......................................... 72
4.2.1. Domain budaya yang berhubungan dengan perilaku politik.... 73
4.2.2. Domain budaya yang berhubungan dengan budaya politik ..... 82
4.2.3. Domain budaya yang berhubungan dengan pewarisan bu-
daya politik ............................................................................... 91
4.3. Budaya Politik MCW dan Reproduksinya .......................................... 101
4.3.1. Budaya Politik MCW .............................................................. 102
4.3.2. Reproduksi Budaya Politik MCW .......................................... 116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 132
5.1. Kesimpulan ......................................................................................... 132
5.2. Saran .................................................................................................... 133
Daftar Pustaka ................................................................................................ 131
Lampiran ........................................................................................................ 133
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya ...... 14
Tabel 2. Peta Posisi NGO ................................................................................ 27
Tabel 3. Contoh Tabel Paradigma .................................................................... 44
Tabel 4. Macam Politik Menurut MCW .......................................................... 73
Tabel 5. Macam Aktivitas Politik MCW ......................................................... 74
Tabel 6. Taksonomi Budaya yang Berhubungan dgn Budaya Politik ............. 83
Tabel 7. Pengimposisian Budaya Politik di MCW .......................................... 92
Tabel 8. Karakteristik Aktivis Menurut MCW ................................................ 99
Tabel 9. Tabel Paradigma Kinds of Activities .................................................. 104
Tabel 10. Tabel Paradigma Kinds of Politics ................................................... 108
Tabel 11. Tabel Paradigma Kinds of Goals ..................................................... 109
Tabel 12. Tabel Paradigma Domain-domain Budaya MCW ........................... 112
Tabel 13. Tabel Paradigma Ways of Cultural Imposition ................................ 117
v
DAFTAR GAMBAR
Bagan 1. Alur Pikir Penelitian ......................................................................... 34
Bagan 2. Struktur Organisasi MCW ................................................................ 53
vi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Standard Operating Procedure MCW
2. Foto-foto
3. Artikel Berita Media Mengenai MCW
vii
ABSTRAK
Gadi Kurniawan Makitan. 2011. Reproduksi Budaya Politik Malang Corruption Watch. Pembimbing utama: Dr. Mardiyono, MPA. Pembimbing Pendamping: Dr. Ratih Nurpratiwi, M.Si.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang budaya
politik apa yang dimiliki organisasi non-pemerintah di tingkat lokal sebagai bagian dari civil society dan bagaimana mereka melakukan reproduksi budaya politik tersebut. Reproduksi budaya politik aktor lokal non-pemerintah adalah hal yang menarik untuk diperhatikan mengingat saat ini mereka mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk mempengaruhi proses politik di daerah.
Tujuan di atas dipenuhi dengan melakukan studi pada salah satu aktor lokal non-pemerintah di Malang, yaitu Malang Corruption Watch (MCW), sebagai salah satu organisasi gerakan masyarakat sipil yang diperhitungkan di Malang. Studi dilakukan dengan metode etnografi, yaitu Teknik Observasi-partisipan 12 Langkah Spradley dan dilandaskan pada perspektif teoritik Pierre Bourdieu tentang reproduksi budaya.
Penelitian dimulai dengan terlibatnya penulis secara aktif dalam segala kegiatan yang dilakukan MCW. Lalu, dalam keterlibatan tersebut, domain-domain budaya yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini berusaha ditemukan. Setelah domain-domain budaya ditemukan, analisis komponensial dilakukan untuk menemukan atribut budaya yang melekat dalam domain-domain budaya itu. Domain budaya beserta atribut budaya yang ditemukan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.
Ditemukan bahwa budaya politik MCW adalah pemosisian dirinya sebagai entitas civil society yang berhadap-hadapan dengan negara; melakukan kegiatan politik untuk mengimbangi kebijakan negara supaya warga negara tidak lagi berada dalam posisi yang lemah. Semua ini didasari keyakinan bahwa demokrasi pasca-soeharto telah ‘dicuri’ oleh elit politik lokal dan aktivitas ‘merebut kembali’ merupakan tindakan yang bertujuan untuk kebajikan. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, MCW melakukan reproduksi budaya politik tersebut melalui pedagogic work (PW) secara implisit dan dilakukan oleh aktor dengan pedagogic authority (PAu). Kata kunci: Reproduksi budaya, civil society, politik
viii
ABSTRACT
Gadi Kurniawan Makitan. 2011. Political Culture Reproduction Of Malang Corruption Watch. Supervisor: Dr. Mardiyono, MPA. Co-Supervisor: Dr. Ratih Nurpratiwi, M.Si.
This research is aimed at giving a description about political culture possesed by local non-government organization as a part of civil society and how they reproduce their political culture. Political-culture reproduction done by local non-state actors is an interesting theme to give attention at regarding the actors’ present huge chance to affect local political process.
The aims above are met by doing a study in a local non-government organizations in Malang, i.e. Malang Corruption Watch (MCW), as a noticeable civil movement in Malang. This study was done by doing ethnography, i.e. Spradley’s 12 steps of participant-observation.
This research started as the writer begun involving actively in MCW’s activities. Then, in the nine months involvement, cultural domains regarding the research’s aims were found. After the cultural domains were found, componential analysis was done to find cultural attributes attached to the cultural domains. The cultural domains along with cultural attributes that had been found were used to answer the research questions.
It was found that MCW’s politicial culture is their positioning as an entity of civil society vis a vis state; doing political activities aimed at balancing state’s power so that civilian will be no longer in marginalised position. All this is based on postulate that Indonesian post-soeharto democracy is being stolen by local political elite and MCW’s activities to ‘take it back’ are activities that have goal on promoting virtue to humankind. In Pierre Bourdieu theoritical perspective, MCW was doing their political culture reproduction through implicit pedagogic work (PW) and was done by an actor with pedagogic authority (PAu). Keywords: cultural reproduction, civil society, politics
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dianggap sebagai titik berangkat
perubahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis. Lebih dari
satu dekade kemudian, beberapa hasil penelitian menemukan bahwa memang
terjadi beberapa perubahan yang tentunya bukan tanpa masalah, khususnya di
tingkat lokal.
Bagaimanapun juga, hal penting yang perlu dilihat di tengah perubahan
berikut masalah yang terjadi dalam demokrasi pasca-Soeharto adalah posisi
birokrasi lokal di Indonesia mengalami pergeseran dari bureaucratic
authoritarian ke bereaucratic pluralism1, di mana itu ditandai dengan makin
terbukanya birokrasi terhadap pressure kekuatan-kekuatan sosial (societal forces)
dalam masyarakat (Zuhro, et al, 2009:4) yang berakibat pada makin terbukanya
kesempatan bagi aktor non-pemerintah untuk mempengaruhi keputusan politik di
suatu daerah.
Aktor lokal non-pemerintah kini bisa memanfaatkan peluang dari adanya
perubahan struktural ini untuk mengetengahkan budaya politik yang sesuai
dengan idealisme mereka di kancah politik lokal. Dengan demikian, pewarisan
1 R. Siti Zuhro menggunakan istilah bureaucratic authoritarian dan bureaucratic pluralism untuk menyebutkan perbedaan kesempatan aktor-aktor lokal untuk mempengaruhi proses politik pada masa Soeharto memerintah dan setelah kejatuhannya. Yang pertama menunjuk pada hampir tidak adanya kesempatan aktor lokal untuk mempengaruhi proses politik di daerahnya karena birokrasi yang begitu terpusat. Yang kedua menunjuk pada terbuka lebarnya kesempatan aktor lokal untuk mempengaruhi proses politik di daerahnya.
2
budaya politik—yang dalam perspektif Pierre Bourdieu disebut dengan
reproduksi budaya—kepada kader-kader organisasi non-pemerintah menjadi
penting. Menarik untuk melihat bagaimana aktor lokal non-pemerintah
melakukan pewarisan budaya politik di dalam entitasnya sendiri.
1.1.1. Transisi Demokrasi dan Masalah di Tingkat Lokal
Bentuk yang paling konkret dari perubahan dalam masa transisi demokrasi
pasca-soeharto adalah devolusi kekuasaan sampai ke tingkat pemerintahan
kota/kabupaten dibarengi juga dengan pemekaran-pemekaran daerah. Perubahan
ini ternyata menimbulkan berbagai masalah. Di beberapa daerah, terjadi kekerasan
komunal. Gerry van Klinken (Klinken, 2007:231-232) mengungkapkan bahwa
devolusi kekuasaan hingga tingkat bawah, dikombinasikan dengan perubahan-
perubahan yang mengarah pada demokratisasi dalam cara penunjukan pejabat
kunci pemerintahan, memicu berbagai dinamika kompetitif yang intens, yang
pada daerah-daerah di luar kota Jawa menimbulkan kekerasan komunal yang
berisukan etnis dan agama. Lemahnya partai-partai resmi sebagai akibat politik
Orde Baru memunculkan kelompok-kelompok etnis dan keagamaan sebagai partai
politik secara de facto. Elit lokal kemudian memobilisasi massa dari jalur etnik
dan agama itu untuk mencari akses istimewa di pemerintahan atau bahkan, jika
mungkin, mengembangkan andilnya.
Di daerah yang lain, di Provinsi Bangka-Belitung dan Banten, misalnya,
muncul fenomena yang disebut dengan shadow-state. Erwiza Erman (2007)
melakukan penelitian di Provinsi Bangka-Belitung. Ia menemukan bahwa
3
otonomi daerah dan pemekaran provinsi khususnya di pulau Bangka dan Belitung
ternyata menjadi peluang besar bagi terbentuknya shadow-state; penguasa
beraliansi dengan pengusaha timah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan
kekuasaan politik mereka dan akibatnya terjadi pembiaran pelanggaran-
pelanggaran seperti perusakan lingkungan.
Ditemukan juga bahwa aktor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
lemah, bahkan menjadi sekutu untuk memihak kepentingan bupati. Namun,
Erman tidak konsisten. Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa negara lemah
sehingga rakyatlah yang mengadili ketidaktegasan pemerintah melalui
demonstrasi-demonstrasi yang diwakili LSM. Tetapi, di sisi lain, ternyata LSM
bersekutu dengan bupati. Apakah memang ada dua macam LSM, yang satu
membela masyarakat, yang lain berpihak pada penguasa? Ini tidak terjawab.
Syarif Hidayat (2007:303) melakukan penelitian di Provinsi Banten, yang
juga merupakan hasil pemekaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa,
“introduksi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada periode pemerintahan pasca-Soeharto telah tidak saja membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, tetapi juga telah membuka ruangan yang lebih luas kepada elit masyarakat (societal actors) untuk membangun dan mengembangkan jaringan informal (informal networks) dengan pada elit penyelenggara pemerintahan di daerah (local-state actors),”
Societal actors dalam kasus Banten ini adalah seseorang yang disebut
Tuan Besar. Ia adalah tokoh Jawara-Pengusaha,2 seorang pengusaha konstruksi
kelas atas. Sebelum Banten berdiri sebagai provinsi, Tuan Besar sering
2 Sebutan populer di kalangan pengamat Banten untuk melabeli individu atau kelompok pengusaha yang pada saat penelitian Syarif Hidayat dilakukan, memiliki pengaruh dominan terhadap para petinggi pemerintah provinsi. Jawara sendiri adalah isitilah yang menunjuk pada sekelompok “jagoan” yang dipercaya memiliki kekuatan magis tertentu yang diperoleh dari Kiai, sehingga mereka sering berfungsi sebagai “pasukan keamanan”
4
berhubungan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani proyek
konstruksi skala besar. Ia juga adalah politisi senior partai Golkar dan pendiri
organisasi jawara terbesar di Banten. Jaringan informal di Banten terbangun
antara Tuan Besar dan politisi lokal. Selain Tuan Besar sering dipercaya
menangani proyek-proyek konstruksi, ia juga membiayai kampanye salah satu
calon gubernur Banten. Ini kemudian menjadi investasi politik di masa depan, di
mana proyek-proyek konstruksi dalam rangka memperkuat infrastruktur Provinsi
Banten yang baru berdiri banyak dimenangkan tendernya oleh perusahaan Tuan
Besar atau perusahaan yang berhubungan dengan Tuan Besar.
1.1.2. Posisi Aktor Non-Pemerintah dalam Transisi Demokrasi di Tingkat Lokal
R. Siti Zuhro (dalam Zuhro, et al., 2009:4) mungkin bisa memberi
perspektif terhadap fakta-fakta di atas khususnya berkaitan dengan posisi aktor-
aktor non-pemerintah dalam proses transisi demokrasi pasca-soeharto dengan
menunjukkan bahwa posisi birokrasi di Indonesia mengalami pergeseran dari
bureaucratic authoritarian ke bureaucratic pluralism, yang itu ditandai dengan
makin terbukanya birokrasi terhadap pressure kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) dalam masyarakat.
Dalam proses pembuatan keputusan politik, kekuatan sosial yang telah
disebutkan di atas memiliki peranan dan pengaruh besar. Tidak ada satu pun
kebijakan publik yang ditetapkan pemda yang lepas dari sorotan atau kritik
masyarakat. Walaupun memang tidak semua sorotan dan kritikan itu
menggagalkan kebijakan daerah, setidaknya aktor non-birokrasi bisa masuk dalam
5
ruang publik. Bahkan, bukan hanya dalam rangka membatalkan kebijakan daerah.
Dalam kasus shadow state di Bangka-Belitung dan Banten, aktor non-pemerintah
bisa mempengaruhi pemerintah untuk membuat keputusan yang menguntungkan
bagi mereka.
Hans Antlov, seperti yang dikutip Zuhro (Zuhro, et al, 2009:7), mencatat
bahwa cukup banyak praktik demokrasi lokal yang telah dijalankan oleh berbagai
kelompok civil society pasca-1999. Ini adalah peran dari Civil Society
Organization (CSO), baik dalam menginisiasi dan memfasilitasi tumbuhnya
berbagai forum warga yang menjadi ruang partisipasi/wadah aspirasi warga,
maupun dalam mendorong berkembangnya aksi-aksi kolektif warga dalam isu-isu
yang lebih struktural.
Selain itu, ditemukan pula bahwa jumlah CSO yang pada jaman Orde Baru
berkisar antara 8.000-10.000 meningkat menjadi 20.000 pada tahun 2000 yang
bergerak di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi dan
litigasi (Hikam, dalam Zuhro, et al, 2009:7). Hasil studi S2 Politik Lokal dan
Otonomi Daerah UGM menunjukkan bahwa aktivitas CSO-CSO itu banyak
berkaitan dengan isu governance reform, termasuk masalah pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah (Zuhro, et al, 2009: 8). Aktor CSO terlihat
semakin diketengahkan, masuk dalam konstelasi politik lokal. Mereka juga dapat
dikatakan sebagai kompetitor (Zuhro, et al, 2009:9).
Berkaitan dengan posisi dan peran CSO dalam konteks demokrasi lokal
pasca-Soeharto ini, Zuhro, et.al (2009:228-230) memberi kesimpulan bahwa
aktor-aktor civil society rentan. Di daerah-daerah yang menjadi lokasi
6
penelitiannya, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Gianyar, Bone, dan Solok, CSO
terfragmentasi, baik dari sisi isu maupun orientasi dan strategi. Dalam hal strategi,
mereka terbagi menjadi dua, antara yang konflik (konfrontatif) dan kolaboratif. Di
Kabupaten Gianyar, CSO yang high politics tidak pernah bersinggungan dengan
CSO di grass-root level. Fragmentasi tersebut, menurut Zuhro et.al, menyebabkan
lemahnya posisi tawar CSO ketika berhadapan dengan kekuatan sosial-politik
lainnya. Dalam kasus Bojonegoro dan Gianyar, CSO cenderung kurang
diperhatikan karena sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal
pembiayaan sehingga kurang kritis terhadap agenda pemerintah daerah. Pada
kasus di Sumatera Barat, CSO bahkan hadir karena mereka diundang dan
dibutuhkan oleh politisi untuk mendukung program dan kebijakannya atau bahkan
untuk memperkuat posisi tawar dengan DPRD, atau yang disebut dengan model
politik invited space.
Jawa Timur disebut Zuhro sebagai daerah yang kepadatan Civil Society
Organization-nya paling padat di antara empat daerah yang ia teliti (Bali,
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan). Ditambahkan pula, semangat arek-nya
memberi pengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan kekuatan
sosial dalam masyarakat (Zuhro, et al., 2009:5).
Malang Corruption Watch (MCW) adalah salah satu aktor CSO di Jawa
Timur, atau yang lebih khusus lagi dikategorikan sebagai non-government
organization (NGO), yang berkiprah di wilayah Malang Raya (Kota Malang,
Kabupaten Malang, dan Kota Batu) dan berdiri pada 31 Mei tahun 2000.3
3 Didapat dari brosur MCW
7
Organisasi ini adalah salah satu contoh NGO yang berstrategi konflik atau
konfrontatif dengan penguasa, yang berkomitmen untuk sama sekali tidak
menerima dana dari pemerintah, yang mereka sebut sebagai objek pantau. MCW
didaulat sebagai simpul jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)4
Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Selain itu, mereka juga adalah koordinator
jaringan anti-korupsi di Jawa Timur.5
Selama lebih dari sepuluh tahun berdiri, MCW tetap konsisten dengan
strategi konfrontatifnya, di mana visinya adalah, “Terciptanya masyarakat madani
yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan
terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.”6 Melihat konsistensi MCW dalam
mempertahankan strategi konfrontatif dan visinya untuk membangun masyarakat
madani yang kuat, jelas bahwa ia merupakan entitas kultur tersendiri atau salah
satu fragmen dalam politik lokal Jawa Timur, secara umumnya, juga dalam
gerakan civil society secara khusus.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pendiri MCW,
yaitu Luthfi J. Kurniawan, diketahui bahwa MCW didirikan oleh aktivis
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sepanjang yang diketahui, HMI merupakan
organisasi yang religius Islam yang moderat. Mereka menolak kebutuhan
didirikannya sebuah negara Islam, dan meyakini bahwa kultur publik bergantung
pada lembaga mediasi yang mengembangkan kebiasaan bebas berbicara,
partisipasi, dan toleransi. Islam demokratis ini yakin bahwa demokrasi formal 4 MP3 adalah koalisi NGO yang berfokus pada isu penciptaan pelayanan publik yang baik 5 Hasil wawancara tanggal 12 Januari 2011 6 Didapat dari brosur MCW
8
tidak akan bisa berlaku kecuali kekuatan pemerintah dikontrol oleh asosiasi-
asosiasi sipil yang kuat (Hefner, 2000:13). Agaknya, ini sesuai dengan visi MCW
yang ingin membangun masyarakat madani yang kuat dan beradab.
Dapat dilihat bahwa MCW sedang berusaha mengetengahkan budaya
humanis dan beradab pada demokrasi lokal Jawa Timur, atau khususnya pada
daerah Malang Raya, dengan penekanan pada keseimbangan antara state dan
society. Mereka tentu juga mewariskan budaya ini dalam diri kader-kadernya.
Dalam istilah Pierre Bourdieu hal ini adalah cultural reproduction. Cultural
reproduction dilakukan dengan kerja pedagogis (pedagogic work) oleh aktor yang
memiliki otoritas pedagogis (pedagogic authority) dan menurut logika Bourdieu,
ini juga menimbulkan social reproduction atau reproduksi kelas. Penelitian ini
membahas proses tersebut dalam entitas Malang Corruption Watch.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam konteks transisi demokrasi dalam politik lokal dan peran aktor
dalam proses transisi yang sudah dijelaskan di atas, khususnya Civil Society
Organization atau yang lebih khusus lagi Non-Goverment Organization (NGO),
penelitian ini ingin menjawab pertanyaan:
a. Budaya politik apa yang dimiliki MCW?
b. Bagaimana reproduksi budaya politik dilakukan MCW sebagai NGO di
kota Malang?
9
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Mendeskripsikan dan menganalisis budaya politik yang sedang
direproduksi MCW.
b. Mendeskripsikan dan menganalisis reproduksi budaya yang terjadi di
Malang Corruption Watch.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1.4.1. Manfaat Akademis
Bagi Sosiologi, penelitian ini bisa menjadi salah satu model penerapan
logika reproduksi budaya Pierre Bourdieu dalam kenyataan empiris. Selain itu,
penelitian ini juga menjadi sumbangsih sosiologis dalam menjelaskan fenomena
transisi demokrasi di ranah lokal dalam era otonomi daerah mengingat kajian
pasca-Soeharto menjadi salah satu mozaik dalam kajian tentang budaya politik
kelas menengah di Indonesia.
1.4.2. Manfaat Praktis
Bagi pembuat kebijakan dan masyarakat, khususnya yang menaruh
perhatian pada konsolidasi demokrasi di Kota Malang, penelitian ini dapat
memberikan gambaran pemetaan gerakan civil society di Kota Malang, sehingga
10
mereka bisa melakukan langkah-langkah yang perlu berkonsolidasi dengan
memajukan demokrasi di Kota Malang.
Bagi institusi yang diteliti, dalam hal ini Malang Corruption Watch,
penelitian ini bisa menjadi sarana refleksi, melihat apa yang selama ini mungkin
tidak disadari. Tentunya ini akan berguna untuk mengevaluasi gerakan mereka
dan bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memajukan
gerakan mereka.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bagian ini, akan dilakukan peninjauan terhadap kepustakaan yang
dapat digunakan sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah. Sesi
pertama akan meninjau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan baik
mengenai budaya politik dan civil society maupun mengenai gerakan Malang
Corruption Watch kemudian mencari relevansi dan juga membandingkannya
dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sesi kedua akan meninjau
kepustakaan yang berbicara mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu Budaya Politik, Civil Society, Reproduksi Budaya, dan
Reproduksi Sosial.
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian kualitatif yang menggunakan pemikiran Pierre Bourdieu yang
penulis acu di sini adalah penelitian Andi Rahman Alamsyah (2007) yang
berjudul Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Studi
tentang Demokratisasi Sedang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004-2006).
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa Habitus politik
agen-agen di Banten tidak hanya dibentuk melalui asal-usul sosial, pekerjaan, dan
pendidikan, namun juga mobilitas sosial dalam ranah ekonomi, politik, dan peer
group. Selain itu, strategi mengubah habitus politik adalah dengan mengubah
modal-modal spesifik, nilai-nilai, lembaga-lembaga, mekanisme kelembagaan,
12
dan lain-lain, pada suatu ranah. Lalu, untuk melihat konteks yang lebih besar,
penulis mengacu pada penelitian Zweiger (2004) dan Mas’oed (2001) yang
membicarakan pengaruh eksternal atau makro terhadap pembentukan budaya
politik.
Berkaitan dengan civil society (CSO, NGO), good governance, dan
budaya politik, ada dua penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama dilakukan
oleh Ivanaly (2007), yang berjudul Peran LSM dalam Mengembangkan Nilai-
Nilai Masyarakat Demokratis (Studi di Malang Corruption Watch). Ada tiga
pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu (1) Bagaimanakah peran LSM MCW
dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis? (2) Kendala-kendala
apakah yang dihadapi MCW dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat
demokratis? (3) Bagaimana upaya LSM MCW dalam menghadapi kendala dalam
mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi lapang, dengan
teknik pengambilan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian
tersebut menyebutkan bahwa tujuan inti dari keberadaan MCW adalah
mewujudkan proses demokratisasi. Dalam mewujudkan demokratisasi ini,
dikatakan bahwa MCW selalu mengedepankan dan menerapkan pengembangan
terhadap nilai-nilai masyarakat demokratis, yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar
warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (trust), dan kerjasama.
Dengan mengembangkan nilai-nilai tersebut, menurut Ivanaly, dapatlah dikatakan
bahwa LSM telah berperan aktif dalam mewujudkan demokratisasi. Dengan kata
13
lain, pertanyaan “bagaimana peran MCW dalam mengembangkan nilai-nilai
demokratis?” dijawab dengan “MCW berperan aktif”. Bagi penulis, dalam
penelitian ini pertanyaan bagaimana belum dijawab secara sosiologis. Selain itu,
teknik pengambilan data yang dilakukan hanya sebatas pada wawancara dan studi
dokumentasi, bukan observasi.
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ikhwan Fahrojih (2004) dengan
judul Partisipasi (LSM) di Era Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan
Good Governance (Studi di MCW dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi-Kolusi).
Pertanyaan penelitiannya adalah (1)Bagaimana partisipasi LSM dalam
mewujudkan good governance di Kota Malang? (2)Faktor-faktor apa yang
menghambat partisipasi LSM dalam mewujudkan good governance di Kota
Malang? (3)Bagaimana solusi agar partisipasi oleh LSM dapat berpengaruh untuk
mewujudkan good governance di Kota Malang?
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, atau dengan
melihat Undang-Undang Partisipasi dan kenyataan lapangannya. Teknik
pengambilan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka undang-undang,
dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi yang dilakukan MCW
dan SORAK7 adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi dan pendidikan
politik anti-korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara preventif dan
represif. Cara preventif dilakukan dengan mendorong DPRD Kota Malang untuk
segera membuat perda tentang partisipasi dan segera mengundangkan undang-
undang perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi. Cara represif
7 SORAK adalah singkatan dari Solidaritas Anti Korupsi yang merupakan forum yang pernah dibentuk MCW namun sekarang sudah tidak ada lagi.
14
dilakukan dengan melakukan advokasi dan investigasi atas kasus-kasus korupsi.
Pendidikan politik dilakukan melalui media massa, forum-forum, dan pendidikan
basis.
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya
Penelitian Metode Temuan Penelitian Zweig. (2004). Political Culture, Alternative Politics and Democracy in Greater China.
kualitatif-deskriptif
• Kekuatan struktural8 memiliki pengaruh terhadap pembentukan budaya politik, seperti budaya Konfusian.
• Budaya politik itu kemudian juga berkaitan dengan struktur politik dan partisipasi politik.
Mas’oed, et al (2001). Social Resources for Civility and Participation: The Case of Yogyakarta, Indonesia.
kualitatif-deskriptif
• Proses modernisasi politik dan sosial yang terjadi secara makro telah membentuk pengalaman hidup warga Yogyakarta dalam level yang paling lokal. Terjadi sebuah revolusi budaya, sehingga Yogyakarta menjadi lebih partisipatif dan pluralis.
Alamsyah (2007). Bantenisasi Demokrasi: Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan (Studi tentang Demokratisasi Serang, Banten, Pasca-Soeharto, Tahun 2004-2006)
kualitatif-deskriptif
• Habitus politik agen-agen di Banten tidak hanya dibentuk melalui asal-usul sosial, pekerjaan, dan pendidikan, namun juga mobilitas sosial dalam ranah ekonomi, politik, dan peer group.
• Strategi merubah habitus politik adalah dengan merubah modal-modal spesifik, nilai-nilai, lembaga-lembaga, mekanisme kelembagaan, dan lain-lain, pada suatu ranah.
Ivanaly (2007). kualitatif- LSM telah berperan aktif dalam
8 Sesuai dengan perspektif Bourdieu, bahwa habitus adalah struktur yang tertubuhkan—sebenarnya tidak ada dikotomi antara tubuh (agen) dan struktur, namun tetap saja aja pembedaan di antara keduanya. Kekuatan ‘struktural’ yang dimaksud di sini adalah struktur sosial/norma yang telah terlembaga.
15
Peran LSM dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Masyarakat Demokratis (Studi di Malang Corruption Watch)
deskriptif mewujudkan demokratisasi dengan cara mengedepankan dan menerapkan pengembangan terhadap nilai-nilai masyarakat demokratis, yang meliputi: • kebebasan menyatakan pendapat, • kebebasan berkelompok, • kebebasan berpartisipasi, • kesetaraan antar warga, • kesetaraan gender, • kedaulatan rakyat, • rasa percaya (trust), • dan kerjasama.
Fahrojih (2004). Partisipasi (LSM) di Era Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di MCW dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi-Kolusi).
kualitatif- deskriptif
Partisipasi yang dilakukan MCW dan SORAK dalam rangka mewujudkan good governance adalah: • melakukan pemberantasan korupsi:
o preventif mendorong DPRD Kota
Malang untuk segera membuat perda tentang partisipasi dan segera mengundangkan undang-undang perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi
o represif melakukan advokasi dan
investigasi atas kasus-kasus korupsi
• pendidikan politik anti-korupsi yang dilakukan melalui media massa, forum-forum, dan pendidikan basis.
Penelitian penulis
kualitatif deskriptif
Berusaha menemukan budaya politik NGO bagaimana mereka melakukan reproduksi budaya di dalam dirinya.
Sumber: olahan pribadi
Penelitian Zweiger dan Mas’oed memberi pandangan awal bahwa budaya
politik bisa terbentuk dari perubahan sosio-kultural yang bersifat makro. Dalam
hal ini, kekuatan struktural bisa berpengaruh. Ini penting untuk melihat konteks
makro apa saja yang melatarbelakangi aktor MCW sehingga nantinya budaya
politik mereka dapat dirumuskan. Kemudian, Alamsyah juga berkontribusi dalam
16
hal menemukan bahwa ternyata mobilitas sosial dan perubahan kelembagaan
politik bisa menyebabkan perubahan budaya politik, atau yang dalam perspektif
Bourdieu dikhususkan lagi menjadi habitus politik. Ketiga hal ini memberi acuan
kepada penulis untuk mempertimbangkan juga faktor eksternal dalam meneliti
budaya politkik MCW.
Dua penelitian selanjutnya, yaitu milik Ivanaly dan Fahrojih, yang lebih
khusus berbicara mengenai MCW memberi acuan kepada penulis mengenai nilai-
nilai politik apa yang dianut MCW dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam
mengetengahkan nilai-niai tersebut. Dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian ini
dengan dua penelitian terdahulu adalah jika dua penelitian sebelumnya melihat
bagaimana MCW mengetengahkan budaya politik ke dalam masyarakat,
penelitian ini melihat bagaimana MCW memproduksi ulang budaya politik itu ke
dalam diri orang-orang yang terlibat di dalamnya.
2.2. Budaya Politik
Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture. Dalam tulisan ini,
penulis menyamakan culture dengan budaya. Koentjaraningrat (2002:181)
menyebutkan bahwa menurut antropologi, kebudayaan berarti keseluruhan sistem
gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat
yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
Budaya dalam hal ini dibedakan dengan peradaban atau civilization. Istilah
civilization digunakan untuk menunjuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari
kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya: kesenian, ilmu
17
pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi
kenegaraan, dan sebagainya, atau juga dipakai untuk menunjuk suatu kebudayaan
yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa,
dan sistem kenegaraan dan masyarakat yang maju dan kompleks.
Honingman dalam Koentjaraningrat (2002: 186-187) menyebutkan ada
tiga gejala kebudayaan. Pertama, ideas; merupakan ide-ide, gagasan, nilai-nilai,
dan norma-norma. Kedua, activities; merupakan aktivitas dan tindakan berpola
dari manusia dalam masyarakat, bersifat konkret dan dapat diobservasi. Ketiga,
artefact; merupakan wujud fisik dari perbuatan dan karya manusia.
Spradley (1979:5) membatasi budaya sebagai pengetahuan yang
didapatkan (dari hasil belajar), yang digunakan untuk menginterpretasikan
pengalaman, dan memunculkan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud
di sini adalah tindakan manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lain.
Dari pengertian-pengertian di atas, penulis membatasi budaya sebagai ide,
gagasan, pengetahuan, yang didapatkan manusia dari hasil belajarnya melalui
interaksi sosial, yang kemudian muncul dalam tindakan-tindakan dan karya-karya
fisik yang konkret dan bisa diobservasi.
Telah didefinisikan secara jelas apa itu budaya. Untuk menuju pada
pembatasan ‘budaya politik’, perlu juga didefinisikan apa itu politik. Rush dan
Althoff (2005:3) menyebutkan bahwa esensi politik adalah sarana-sarana dengan
mana manusia memecahkan permasalahannya bersama-sama dengan manusia
lain. Crick dalam Rush dan Althoff (2005:3) menyatakan bahwa masalah tersebut
adalah pemerintahan, dalam pengertian “aktivitas memelihara kententraman”.
18
Budiardjo (2004:8) mengatakan bahwa pada umumnya, dapat dikatakan
bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu. Ini berkaitan juga dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari
sumber-sumber yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh
masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).
Sedangkan Surbakti (1995: 11) mendefinisikan politik sebagai interaksi antara
pemerintah dan masyarkat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal
dalam suatu wilayah tertentu. Maka, segala perilaku yang bersangkutan dengan
proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik disebut
perilaku politik.
Melihat batasan-batasan di atas, ‘budaya politik’ dapat didefinisikan
sebagai sebagai ide, gagasan, pengetahuan mengenai sarana-sarana dengan mana
manusia mengatur kehidupan bersama yang baik di dalam suatu sistem negara—
yang didapatkan dari hasil belajarnya melalui interaksi sosial, yang kemudian
muncul dalam tindakan-tindakan dan karya-karya fisik yang konkret dan bisa
diobservasi. Dengan kata lain, budaya politik merupakan pengetahuan yang
mendasari perilaku politik tertentu.
Ide, gagasan, pengetahuan tentang bagaimana ‘bernegara yang baik’ itu
tentu bermacam-macam. Penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh
Douglas E. Ramage tentang ideologi politik yang dimiliki masyarakat Indonesia,
19
yang kemudian dibukukan dengan judul Politics in Indonesia: Democracy, Islam,
and The Ideology of Tolerance (1995). Ramage melakukan wawancara dengan
jangkauan yang sangat luas, dengan 175 informan, meliputi menteri, angkatan
bersenjata, birokrat senior, intelektual dan aktivis muslim, pemimpin dari 3 partai
politik (saat itu Golkar, PDI, dan PPP), ideolog, pensiunan militer dan
pemerintahan, pemimpin minoritas agama dan etnis, akademisi, jurnalis,
pengacara, dan aktivis demokrasi dan HAM.
Ramage menemukan sedikitnya ada ‘four general voices’, yaitu: mereka
yang mewakili pandangan Abdurrahman Wahid, pemimpin NU (saat itu), mereka
yang berafiliasi dengan ICMI, angkatan bersenjata, dan yang terakhir nasionalis
sekuler, yang kebanyakan adalah aktivis demokrasi dan HAM. Yang terakhir
agaknya sesuaikan dengan subyek penelitian ini yaitu Malang Corruption Watch,
yang dapat dikatakan adalah aktivis demokrasi. Kebanyakan aktivis demokrasi
mendorong demokratisasi yang lebih baik dan mempertahankan toleransi
beragama Pancasila sebagai dasar dari negara. Pada level yang umum, nasionalis
sekuler berpendapat bahwa agama dan afiliasi “primodial” lainnya adalah jalan
yang tidak tepat untuk menyalurkan aspirasi politik. Nasionalis sekuler juga
berpendapat bahwa warga negara Indonesia harus diperlakukan sama oleh
pemerintah. Tiap warga negara adalah sama di hadapan hukum, tidak peduli
agama dan etnisnya. Mereka juga berpendapat bahwa toleransi beragama dan
kesederajatan tiap warga negara sangat berhubungan dengan terpeliharanya
kesatuan nasional Indonesia. Perhatian utama para nasionalis sekular adalah juga
pada demokratisasi dan transparansi politik. Mereka ingin dominasi politik militer
20
berkurang, tetapi juga ingin militer tetap menjalankan fungsinya sebagai penjamin
kesatuan nasional dan hak-hak warga negara. Mereka juga menolak Islam sebagai
basis negara.
Demokratisasi yang dimaksud di sini secara sederhana bisa diartikan
sebagai jalan atau perubahan dari rezim non-demokratis menjadi rezim
demokratis.9 Syarat utama dari proses itu adalah kehadiran kekuatan-kekuatan
penekan yang teroganisir dan relatif mandiri dari kontrol negara, yang merupakan
bagian dari civil society. Ini memungkinkan partisipasi politik secara luas melalui
sistem pemilihan yang kompetitif dan transparan yang diharapkan dapat
menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif serta pemerintahan yang
baik, bersih, dan akuntabel, yang sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan
bersama. (Zuhro, et al, 2009:xviii,16). Artinya, nasionalis sekular juga berjuang
untuk pemerintahan yang bersih dan baik (good governance), sebagai salah satu
tujuan demokrasi.
Selain budaya nasionalis sekuler, peninjauan juga dilakukan terhadap
budaya kaum modernis Islam dalam memandang politik, sebagaimana diketahui
bahwa pendiri MCW adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
di mana HMI adalah organisasi yang dekat dengan kaum modernis Islam.
Kaum modernis Islam, terbagi menjadi dua, yaitu yang formalis dan yang
substansialis (Prasetyo, et al, 2002:240-241). Keduanya memandang Islam
sebagai agama yang sempurna, yang menuntun kepada kehidupan yang baik.
9 Terdapat beberapa pandangan mengenai indikator apakah sebuah rezim bisa dikatakan demokratis atau tidak. Namun, yang senada dari pandangan-pandangan itu adalah ciri partisipasi (Almond dan Verba, dalam Zuhro et al, 2011:33). Artinya, salah satu indikator penting adalah terjaminnya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan politik.
21
Bedanya, yang pertama mengimplikasikan kesempurnaan itu dengan
diharuskannya Islam menjadi ideologi negara dan bahkan bentuk negara. Yang
kedua mengimplikasikan kesempurnaan itu lebih dengan menanamkan nilai-nilai
Islami di masyarakat, bukan dengan secara formal ingin mengideologisasikan
Islam atau mengetengahkan simbol-simbol Islam di dalam masyarakat. Yang
kedua ini menekankan pemisahan antara agama dan negara; antara wilayah Tuhan
dan manusia; antara yang transedental dan temporal.
Kaum modernis-substansialis menekankan pentingnya umat Islam
berjuang bukan hanya bagi kepentingan orang beragama Islam, tetapi juga
kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pendapat mereka tentang
bagaimana seharusnya kehidupan bersama dalam suatu negara dijalankan bisa
ditelusuri dari ideal Nurcholis Madjid tentang civil society yang diterjemahkan
menjadi masyarakat madani.
Masyarakat madani...mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamaddun (civility). Sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Ini berarti, tidak ada satu pihak mana pun, termasuk pemerintah...yang berhak memaksakan kehendak dan kemauannya sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi, regimentasi...yang pada gilirannya hanya menimbulkan lawlessness dengan social cost yang amat mahal. (Madjid, dalam Prasetyo, et al, 2002:174)
Selain hal-hal di atas, menurut Nurcholish Madjid, ada elemen-elemen
penting yang harus diperjuangkan dalam masyarakat madani, yaitu supremasi
hukum yang tanpa pandang bulu. Ini mensyaratkan adanya bentuk interaksi sosial
yang memberikan peluang bagi adanya pengawasan dari masyarakat terhadap
negara. Aspek yang lain adalah pluralisme, sebagai “suatu unsur amat asasi dalam
22
masyarakat madani sebagaimana diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi.” (Madjid,
dalam Prasetyo, et al, 2002:176).
2.3. Civil Society
Batasan mengenai apa yang disebut dengan civil society berkembang dari
jaman pra-modern, modern, hingga pos-modern. Pada jaman filsuf seperti
Sokrates dan Plato, civil society dimaknai sebagai ideal good society, tempat di
mana konflik diresolusikan dan juga tempat di mana nilai-nilai kebijaksanaa,
keberanian, dan keadilan dipraktekkan. Civil society di sini tidak dibedakan
dengan negara. Pembedaan antara civil society dan negara dimulai pada jaman
modern, di mana Hegel melihat civil society sebagai komunitas pasar, yang
berbeda dari negara. Kemudian Karl Marx melihat civil society sebagai
masyarakat borjuis, yang menindas manusia yang karena itu harus dilenyapkan.
Antonio Gramsci melihat civil society sebagai tempat perebutan posisi hegemonik
di luar kekuatan negara.
Kemudian, Alexis de Tocqueville mengembangkan pemikiran civil society
sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Pandangan inilah yang menjadi
dasar berkembangnya pemikiran civil society pada era posmodern, terutama di
Eropa Tengah dan Timur, di mana civil society dilhat sebagai the third sector, di
samping negara dan pasar. Civil society dilihat sebagai obat dari dominasi negara
yang melemahkan masyarakat. Khususnya di negara berkembang, civil society
hadir sebagai wilayah di mana perjuangan untuk melindungi masyarakat dari
dampak negatif globalisasi dilakukan.
23
Sedikitnya ada tiga definisi mengenai civil society yang bisa ditelusuri dari
pemikiran intelektual Eropa dan Asia (Rosyada, et al, 2003:238-240). Pertama,
Zbigniew Rau, dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan
Uni Soviet, menyebutkan civil society merupakan suatu masyarakat yang
berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan
perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai
nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan
yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang
menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Maka, yang dimaksud dengan
civil society adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan
kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam
masyarakat madani ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni
individualisme, pasar, dan pluralisme.
Kedua, Han Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan,
mengatakan bahwa civil society merupakan sebuah kerangka hukum yang
melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang
terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu
politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen,
yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi
identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya terdapat kelompok
inti. Hal ini menekankan pada adanya ruang publik, serta mengandung empat ciri
dan prasyarat bagi terbentuknya civil society, yakni pertama, diakui dan
dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari
24
negara. Kedua, adaya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa pun
dalam mengartikulasikan isu-isu politik. Ketiga, terdapatnya gerakan-gerakan
kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. Keempat, terdapat
kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat
yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi ekonomi.
Sedangkan, ketiga, menurut Kim Sunhyuk, yang dimaksud dengan civil
society adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara
mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara
relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi
dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan dalam suatu ruang
publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-
kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang
mandiri.
Benang emas dari ketiga definisi di atas menyatakan bahwa civil society
adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di
hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan
pendapat, dan adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan
aspirasi dan kepentingan publik.
Di Indonesia, di samping civil society, memang istilah yang populer adalah
masyarakat madani. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, Nurcholis Madjid
atau Cak Nur yang berkontribusi dalam memaparkan suatu pemikiran mengenai
masyarakat madani—yang dalam pengamatan penulis sering dikutip oleh aktor-
aktor di MCW.
25
Muhammad AS Hikam menggunakan istilah civil society tanpa
menerjemahkannya. Pengertian civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan
sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan,
keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan
negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti
oleh warganya. Sebagai ruang politik, civil society merupakan suatu wilayah yang
menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak
terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam
jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya
suatu ruang publik yang bebas. Tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas
bisa dilakukan oleh warga masyarakat.
Rosyada, et al, (2003:242) menyebutkan bahwa pengertian ini semua
bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas
negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara (policy of
state) yang cenderung memposisikan warga negara sebagai subjek yang lemah.
Sebagai implikasinya, lembaga swadaya masyarakat merupakan komponen yang
penting dalam civil society.
Dari definisi-definisi di atas, dengan disesuaikan pada konteks Indonesia,
penulis melihat melihat bahwa civil society bisa dibatasi sebagai suatu ruang
sosial yang mandiri dari negara dan mengorganisasikan dirinya sendiri dengan
nilai-nilai tertentu. Ruang yang mandiri dari negara itu bisa muncul sebagai reaksi
atas dominasi negara dan pasar.
26
Organisasi yang terbentuk dari ruang tersebut di atas dinamakan Civil
Society Organization (CSO). Konsep Civil Society Organization (CSO) dan Non-
Goverment Organization (NGO) perlu dibedakan (Atkinson dan Scurrah, 2009;
Weller, 2005). Civil Society Organization (CSO) adalah organisasi yang mana
warga negara biasa bekrumpul bersama untuk memajukan sebuah kepentingan
yang mereka sama-sama mereka miliki, yang dirasakan secara kuat sehingga
mereka ingin melakukan aksi kolektif. Mereka adalah organisasi, asosiasi
jaringan, dan komunitas nir-laba yang formal dan informal. Masing-masing
mempunyai isu dan ranah tertentu yang menjadi perhatian mereka. Yang termasuk
di dalamnya adalah persatuan buruh dan koperasi petani, kelompok-kelompok
wanita, asosiasi konsumen, sampai kepada asosiasi profesional atau akademis.
Yang tidak termasuk di dalanya adalah pemerintah dan organisasi bisnis.
Non-goverment organization (NGO) adalah bagian dari CSO. Mereka
lebih terbentuk dan terorganisasi secara formal, biasanya independen (tidak di
bawah struktur negara) dan nir-laba. Istilah ini dibatasi untuk organisasi yang
memiliki agenda keadilan sosial yang eksplisit. Perhatian utamanya adalah
meningkatkan kualitas hidup orang miskin, mempromosikan hak asasi manusia,
tata pemerintahan yang lebih baik, atau perlindungan lingkungan.
NGO menyediakan pelayanan atau melakukan advokasi untuk
mengetengahkan isu tertentu atau untuk melakukan perubahan tertentu. Biasanya,
mereka dipimpin oleh pengurus yayasan, bukan oleh perwakilan terpilih dari
konstituen, dan pendapatan utamanya didapat dari donasi sukarela. Semua NGO
adalah CSO, tetapi tidak semua CSO adalah NGO. Kelompok-kelompok
27
representatif seperti persatuan buruh atau asosiasi petani yang adalah perwakilan
terpilih dari konstituen tertentu tidak termasuk dalam NGO. Organisasi dari
masyarakat lokal yang berkumpul karena masalah sama yang dialami atau
kekecewaan tertentu juga adalah CSO tetapi bukan NGO.10
Mengenai NGO, ada juga pembedaan yang perlu dilakukan untuk melihat
posisi MCW. Pembedaan ini berkaitan dengan pilihan posisi NGO di hadapan
pemerintah, seperti yang tampak dalam tabel berikut:
Tabel 2. Peta Posisi NGO
NO ITEM KONFRONTASI REKLAIM ENGAGEMENT 1 Aliran Kiri Kiri baru Konvergensi kanan-
kiri (Kiri tengah) atau liberal yang kiri
2 Konsep utama Gerakan sosial Strong democracy (participatory democracy)
Good governance atau democratic, demokrasi deliberatif, governance dan citizenship.
3 Asumsi dasar tentang negara
1) Negara adalah sumber dari segala sumber masalah 2) rakyat tidak bisa berbuat salah
Negara telah berubah karena demokratisasi, tetapi ia masih dikuasai oligarki elite.
Negara sangat penting dan dibutuhkan, tetapi kapasitas dan responsivitasnya sangat lemah
4 Konteks/kondisi empirik
Negara dikuasai oleh penguasa otoriter, korup dan berpihak pada pemodal
Demokrasi dibajak oleh kaum elite. Terjadi krisis dan involusi demokrasi perwakilan
Oligarkis, komitmen politik lemah, partisipasi warga sangat lemah.
5 Tujuan dan agenda
Melawan negara, meruntuhkan penguasa otoritarian, melawan kebijakan
Memperdalam demokrasi dan merebut jabatan publik untuk mengontrol
Membuat negara lebih akuntabel dan responsif, serta memperkuat partisipasi warga.
10 Pembedaan ini dilakukan berdasarkan kategorisasi yang dilakukan oleh Atkinson dan Scurrah, 2009, dan Weller, 2005
28
yang tidak pro rakyat
negara.
6 Strategi utama Aksi kolektif Memperkuat CSOs, gerakan politik dan representasi
Konsultasi, komunikasi, negosiasi yang dialogis antara CSOs dan negara.
Sumber: Sutoro Eko, dalam Kurniawan, Luthfi J., et al (2008:125)
Dari tabel di atas, terdapat tiga kategori posisi NGO dalam hubungannya
dengan pemerintah. Pilihan posisi itu berkaitan dengan asumsi-asumsi dasar yang
dipercayai yang kemudian berpengaru pada pilihan strategi mereka. Pertama,
pilihan posisi konfrontatif. Pada posisi ini, NGO berasumsi bahwa negara adalah
sumber dari segala masalah dan rakyat tidak pernah salah. Asumsi yang lain
adalah bahwa negara dikuasai oleh penguasan otoriter, korup, dan berpihak pada
pemodal. Oleh karena itu agenda dan strategi utamanya adalah aksi kolektif untuk
melawan negara, meruntuhkan penguasa otoritarian, dan melawan kebijakan yang
tidak pro-rakyat. Kedua, pilihan posisi reklaim. Pada posisi ini, NGO berasumsi
bahwa negara memang telah berubah karena demokratisasi, tetapi ia masih
dikuasai oligarki elit. Oleh karena itu, agenda dan strategi utamanya adalah
memperkuat organisasi masyarakat sipil, gerakan politik dan representasi untuk
memperdalam demokrasi dan merebut kekuasaan atau menduduki jabatan publik.
Ketiga, pilihan posisi engagement. Asumsi dasarnya adalah bahwa negara sangat
penting dan dibutuhkan, tetapi kapasitas dan responsivitasnya sangat lemah dan
masih bersifat oligarkis dengan komitmen politik lemah dan partisipasi warga
negara lemah. Oleh karena itu, agenda dan strategi utamanya adalah konsultasi,
komunikasi, dan negosiasi yang dialogis antara masyarakat sipil dan negara untuk
29
membuat negara lebih akuntabel dan responsif, dan juga memperkuat partisipasi
warga negara.
2.4. Reproduksi Budaya dan Reproduksi Sosial
Cambridge Dictionary of Sociology mendefinisikan reproduksi budaya
(cultural reproduction) sebagai proses mentransmisikan modal budaya melalui
pewarisan. Ini mengimplikasikan pewarisan sebuah budaya dari generasi ke
generasi. Selain itu, bagi Bourdieu, reproduksi budaya juga memiliki fungsi
reproduksi sosial (Jenkins, 1992:66). Bourdieu mengartikan reproduksi sosial
sebagai reproduksi relasi di antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas
(Bourdieu, 1990:54). Kata reproduksi digunakan karena ini menunjuk pada
kegiatan produksi yang terus-menerus atau dilakukan berulang-ulang. Relasi yang
dimaksud adalah stratifikasi sosial, bahwa ada perbedaan kelas. Ini sebagai
dampak dari distribusi modal yang tidak merata.11
2.4.1. Reproduksi Budaya
Dalam cara pandang Pierre Bourdieu, pewarisan budaya tidak lain adalah
pewarisan modal budaya, yaitu habitus. Maka, habitus merupakan hal yang
penting dalam pewarisan budaya atau reproduksi budaya. Bourdieu mengartikan
habitus sebagai sistem karakter yang tahan lama, bisa diubah, struktur yang
berfungsi untuk membuat struktur, sebagai prinsip-prinsip yang memunculkan
11 Bourdieu mengikuti logika Karl Marx bahwa kelompok-kelompok sosial berhubungan dalam keadaan distribusi modal yang tidak merata. Kelompok yang satu memiliki modal yang lebih dari yang lain dan sebaliknya. Maka, muncullah kelas sosial. Dengan kata lain, reprduksi sosial bisa juga dikatakan reproduksi eksistensi kelas.
30
dan mengatur perilaku yang bisa secara objektif disesuaikan dengan hasilnya
namun tanpa sebuah kesadaran untuk mencapai tujuan atau sebuah penguasaan
dari operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Dengan kata lain,
habitus merupakan “spontaenity, without consciousness or will.” (Bourdieu,
1990:56).
Habitus dihasilkan dari proses yang disebut Bourdieu sebagai pedagogic
work (PW), yaitu
a process of inculcation which must last long enough to produce a durable training, i.e. a habitus, the product of internalization of the principles of a cultural arbitrary capable of perpetuating itself after PA (pedagogic action)12 has ceased and thereby of perpetuating in practices the principles of the internalized arbitrary. (Bourdieu dan Passeron, dalam Jenkins, 1992:67)
Yang melakukan baik PW maupun PA adalah agen yang memiliki
pedagogic authority (PAu), yaitu kekuasaan untuk bertindak, yang dialami
sebagai sesuatu yang sah oleh penerima perlakuan itu. Tindakan yang dilakukan
oleh agen dengan PAu akan dialami sebagai sesuatu yang positif bagi orang-orang
yang menerimanya. Hampir seperti hubungan orang tua dengan anak. Ia dianggap
sebagai ‘mandated representative’ dari kelompok yang mengimposisikan sebuah
kultur. (Jenkins, 1992:66).
12 Pedagogic action (PA) sendiri adalah praktek imposisi budaya. Istilah imposisi yang digunakan di sini penulis serap dari bahasa Inggris imposition, yang arti harfiahnya adalah pembebanan. Dalam konteks pembicaraan ini, imposisi bisa diartikan sebagai pewarisan budaya, jika ‘pembebanan budaya’ sebagai pengartian harfiahnya dirasa tidak cocok. Imposisi budaya itu terjadi dalam tiga modus. Pertama, diffuse education, yang dilakukan dalam serangkaian interaksi dengan anggota-anggota yang kompeten dari formasi sosial tertentu, misalnya peer group. Kedua, family education, yaitu pendidikan yang dilakukan dalam keluarga. Ketiga, institusionalised education, seperti sekolah dan yang lainnya.
31
Pedagogic work dapat diklasifikasikan menjadi yang implisit dan eksplisit
(Jenkins, 1992:68). Yang dimaksud implisit adalah proses penanaman prinsip
yang secara tidak sadar dilakukan yang nyata hanya dalam praktek-praktek. Yang
dimaksud eksplisit adalah proses penanaman yang secara metode terorganisir,
bahkan diformulasikan dalam prinsip-prinsip.
Bourdieu menyatakan bahwa habitus itu, “Objectively ‘regulated’ and
‘regular’ without being in any way the product of obedience to rules, they can be
collectively orchestrated without being the product of obedience to rules, they can
be collectively orchestrated without being the product of the organizing action of
a conductor.” (Bourdieu, 1990:53). Dengan kata lain, seseorang atau sekelompok
orang yang memiliki habitus memiliki kemerdekaan tersendiri, bahwa mereka
melakukan sesuatu—walaupun hal itu adalah sesuatu yang teratur—tanpa diatur,
atau Bourdieu membahasakannya dengan: “tanpa menjadi sebuah produk dari
aturan-aturan.”
Kemerdekaan itu bisa terjadi karena habitus tidak lain merupakan, “the
active presence of the whole past of which it is the product”(Bourdieu, 1990:53)
sehingga, “it is what gives practices their relative autonomy with respect to
external determinations of the immediate present.” Jadi, sekalipun seorang atau
sekelompok aktor ditekan dengan kondisi sosial saat ini, ia tetap memiliki
kemerdekaan dalam bertindak karena tindakannya itu tidak lain dipengaruhi oleh
masa lalunya. Masa lalu atau sejarah itu berfungsi sebagai accumulated capital.
Seorang atau sekelompok individu bisa menjadi agen yang memiliki dunia
tersendiri di dalam dunia tempat mereka berada.
32
Tindakan seorang atau sekelompok individu tidak sepenuhnya
dideterminasi oleh kondisi yang sekarang namun mereka juga tidak sepenuhnya
secara sadar menentukan tindakan mereka berdasarkan tujuan yang ingin dicapai
atau penguasaan-penguasaan tertentu dari tujuan yang hendak dicapai. Mereka
bertindak secara spontan karena dipengaruhi masa lalu yang mana Bourdieu
mengistilahkannnya dengan ‘spiritual automaton’. Jadi mereka merdeka dari
masa kini namun tidak merdeka dari masa lalu atau sejarah yang membentuk
mereka.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prasyarat adanya habitus yang
sama dalam sekelompok individu adalah sebuah collective history atau
pengalaman masa lampau yang sama. Atau dengan kata lain, habitus merupakan
“incorporation of the same history.” (Bourdieu, 1990:58)
Dengan demikian, sangat dimungkinkan adanya habitus yang sama atau
sesuai di antara sekelompok orang. Habitus yang sama bisa disebut dengan
habitus kelas atau habitus kelompok. Bordieu memberi definisi habitus kelas
sebagai berikut.
Class (or group) habitus, that is, the individual habitus in so far as it expresses or reflect the class (or group), could be regarded as a subjective but non-individual system of internalized structures, common schemes of perception, conception and action, which are the precondition of all objectification and apperception; and the objective co-ordination of practices and the sharing of a world-view could be founded on the perfect impersonality and interchangeability of singular pratices and views.(Bourdieu, 1990:60)
Ciri utama habitus kelas adalah adanya persepsi, konsepsi, dan aksi yang
sama dalam setiap anggotanya. Yang penulis maksudkan dengan persepsi adalah
kemampuan menangkap fakta yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan yang penulis
33
maksud dengan konsepsi adalah kemampuan membangun suatu skema berpikir
setelah menangkap fakta yang kemudian akan menghasilkan tindakan.
2.4.2. Reproduksi Sosial
Didasarkan pada hasil survey dan studi kasus pada mahasiswa Fakulttas
Seni di Lille dan Paris, Bourdieu menulis buku yang berjudul The Inheritors, yang
membahas produksi dan reproduksi warisan budaya. Dalam buku itu, Bourdieu
membahas bagaimana ada mahasiswa yang merasa nyaman (feel at home) dan ada
yang tidak. Mahasiswa yang cenderung merasa nyaman dengan sistem pendidikan
itu adalah mereka memiliki latar belakang keluarga yang mendidik mahasiswa
tersebut untuk memiliki disiplin dan sikap terhadap pendidikan yang sesuai
dengan universitas tersebut. Sedangkan mahasiswa yang tidak memiliki didikan
keluarga seperti itu, akan cenderung merasa tidak nyaman. Tentunya, yang
memiliki prestasi yang lebih baik adalah mereka-mereka yang merasa nyaman. Di
sinilah kesenjangan kesenjangan kelas terjadi. Bourdieu berpendapat bahwa
sistem pendidikan itu menyembunyikan privilise dengan mengabaikannya.
Mereka seakan-akan memperlakukan setiap orang sama (sejajar). Padahal, semua
kompetitor memulai dengan ‘modal’ (habitus) yang berbeda, (Jenkins, 1992:70).
Sehingga, mereka yang tidak nyaman akan tereksklusi dengan sendirinya tanpa
harus dieksklusi.
Inilah yang disebut dengan reproduksi sosial, yaitu reproduksi relasi di
antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas (Bourdieu, 1990:54). Stratifikasi
sosial atau kelas akan tetap ada karena praktek pengimposisian budaya dalam
34
suatu institusi akan menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki habitus yang
sesuai akan dengan sendirinya tereksklusi dan pada akhirnya tidak bisa menjadi
bagian dari kelas tersebut.
2.5. Alur Berpikir
PW
(1)
Reproduksi Sosial terjadi sebagai akibat
reproduksi budaya
MCW melakukan reproduksi budaya
Malang Corruption
Watch
Kader MCW
Explicit Education
Habitus Budaya Politik MCW
Orang-orang
Implicit Education
PAu (LJK)
‘Politik Nilai’
Kredit Simbolik
(2)
(3)
(4)
35
Bagan di atas menggambarkan bagaimana reproduksi budaya politik
dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW), yang mempraktikkan ‘politik
nilai’, yaitu gerakkan melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan negara, untuk
membela warga negara yang dianggap dirugikan, dengan tujuan kebajikan.
Malang Corruption Watch memberikan kredit simbolik kepada seorang
aktor sehingga ia memiliki PAu (pedagodic authority), yaitu otoritas untuk
bertindak dan berkata-kata mengatasnamakan MCW dan dianggap sah (1).
Otoritas itu memberikan dia kekuasaan untuk melakukan pedagogic work (PW)
yang terdiri dari implicit education dan explicit education (2). Hasil dari
pedagogic work tersebut adalah habitus budaya politik yang ideal menurut MCW
(3). Berdasarkan logika Bourdieu, praktek reproduksi budaya politik tersebut juga
secara langsung mengakibatkan terjadinya seleksi habitus (digambarkan dengan
kotak dengan garis putus-putus) sehingga hanya orang-orang yang memiliki
habitus yang cocok saja (atau yang bisa menyesuaikan habitus-nya dengan
habitus yang diketengahkan dalam organisasi itu) yang bisa masuk sebagai
anggota dan menjadi kader MCW. Inilah yang disebut dengan fungsi reproduksi
sosial (reproduksi kelas) dari reproduksi budaya (4).
36
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif karena bertujuan untuk
mendalami sebuah latar sosial tertentu, membuat rangkaian kategori-kategori,
mengklasifikasikan jenis, mengklarifikasi sekuens atau langkah-langkah,
mendokumentasikan mekanisme suatu fenomena terjadi, dan melaporkan latar
atau konteks dari sebuah situasi (Neuman 2007:15). Data yang ditampilkan
bersifat kualitatif, yaitu kata-kata dan gambar, ditampilkan baik dalam narasi
maupun bagan.
Lebih khusus, teknik penelitian ini adalah studi lapang (field research)
atau observasi-partisipatif (participant-observation research) atau etnografi, di
mana seorang peneliti secara langsung mengobservasi dan berpartisipasi di dalam
latar sosial berskala kecil (Neuman, 2007:276).
3.2. Penetapan Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian etnografi adalah situasi sosial, yang
bisa diidentifikasikan dengan tiga elemen dasar, yaitu tempat, aktor, dan aktivitas
(Spradley, 1980:39). Dalam penelitian ini, penulis memilih Malang Corruption
Watch. Malang Corruption Watch dipilih karena ia merupakan tempat di mana
reproduksi budaya politik civil society dilakukan di Malang. Di dalamnya terdapat
37
aktor-aktor yang menjadi pelaku praktek reproduksi budaya tersebut yang
tentunya melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat dioberservasi.
Selain lokasi secara geografis, penulis juga menentukan lokasi waktu,
yaitu sesuai dengan kurun waktu dilakukannya observasi partisipan, yaitu pada
bulan Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011. Artinya pertanyaan penelitian
hanya akan dijawab berdasarkan data yang diperoleh selama kurun waktu
tersebut.
3.3. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah menemukan budaya politik apa yang ada di
dalam Malang Corruption Watch (MCW) sebagai salah satu entitas civil society di
Malang. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana budaya politik itu
direproduksi di dalam diri aktor-aktor MCW.
Mengenai reproduksi sosial yang terjadi, penulis tidak akan membahasnya
secara terperinci dengan menceritakan setiap orang yang memutuskan tidak
bergabung lagi di MCW. Kenyataan reproduksi sosial itu ditampilkan hanya
untuk menunjukkan bahwa ada konsekuensi logis dari reproduksi budaya yang
dilakukan MCW; bahwa ada orang-orang yang bertahan dan ada yang tidak.
Fokus penelitian di atas juga akan membatasi penulis untuk tidak
membahas bagaimana MCW melakukan pertarungan simbolik dalam kancah
politik lokal Malang atau memetakan bobot relatif modal-modal yang dimiliki
MCW, sekalipun kedua hal tersebut adalah kajian Pierre Bourdieu.
38
3.4. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini adalah pengamatan peneliti yang
dituangkan dalam catatan lapangan (field notes) dan hasil wawancara. Sebagai
tambahan, peneliti juga mengambil data dari dokumentasi-dokumentasi tentang
Malang Corruption Watch.
3.5. Proses Pengumpulan Data
a. Observasi
Penelitian ini menggunakan langkah-langkah observasi yang
diajukan Spradley (1980), yang disebut dengan Developmental Research
Sequence.
(1) Memilih situasi sosial
Penelitian dimulai dengan menentukan situasi sosial (tempat, aktor,
aktivitas) mana yang ingin diteliti.
(2) Melakukan observasi-partisipatif
Setelah menentukan situasi sosial yang hendak diteliti, langkah
selanjutnya adalah terlibat dalam situasi sosial yang telah dipilih. Penulis
terlibat sebagai relawan di Malang Corruption Watch dan sejak bulan
Oktober tahun 2010 sampai sekarang, penulis masih aktif sebagai relawan
dan terus melakukan pengamatan.
39
(3) Membuat catatan etnografis
Dalam melakukan observasi, perlu dibuat catatan atau rekaman
etnografis. Adau empat tipe catatan. Yang pertama, condensed account,
yaitu catatan singkat yang berisi hal-hal yang mengingatkan peneliti,
seperti frase, kata, atau kalimat-kalimat yang tidak berhubungan. Catatan
ini berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat catatan tipe kedua, yaitu
expanded account, yang berisi catatan lengkap atau rekaman dari sesi
lapangan yang telah dilalui. Yang ketiga adalah fieldwork journal, atau
buku harian yang merekam emosi-emosi yang dialami peneliti, segala
pikiran atau kekalutan yang dialami. Yang keempat, analysis and
interpretation, yaitu catatan yang berisi interpretasi atas expanded account
(4) Membuat observasi deskriptif
Observasi deskriptif adalah melakukan deskripsi atas sebuah
situasi sosial, dan mencoba merekam sebanyak-banyaknya. Bagian ini
telah penulis lakukan semenjak bulan Oktober 2010, saat penulis mulai
terlibat sebagai relawan MCW. Deskripsi ini menjabarkan sedikitnya
sembilan aspek dalam sebuah siatuasi sosial, yaitu tempat, aktor yang
terlibat dan perannya, aktivitas yang dilakukan, objek-objek fisik yang
ditemukan, aksi tunggal yang dilakukan individu, event, waktu, tujuan, dan
perasaan-perasaan orang yang terlibat dalam situasi sosial tersebut.
40
(5) Melakukan observasi terfokus
Sebuah fokus mengacu pada satu domain budaya atau serangkaian
domain yang berhubungan dan relasi dari satu atau serangkaian domain
budaya itu dengan seluruh cultural scene. Ada beberapa kriteria untuk
memilih fokus observasi dan salah satu di antaranya adalah ketertarikan
terhadap teori tertentu. Kriteria inilah yang penulis gunakan dalam
memilih fokus observasi. Ketertarikan penulis terhadap teori reproduksi
budaya dan reproduksi sosial Pierre Bourdieu-lah yang menjadi dasar
penentuan fokus observasi penulis.
b. Wawancara
Sekalipun teknik penelitian yang dilakukan berbasis pengamatan,
dalam kerangka Developmental Research Sequence Spradley, kegiatan
wawancara juga dilakukan; namun dalam porsi yang sangat kecil.
Wawancara formal hanya penulis lakukan sebanyak tiga kali. Selebihnya,
penulis mengamati semua kata-kata dan kalimat yang keluar saat
perbincangan-perbincangan informal terjadi.
Wawancara formal dilakukan untuk menanyakan perbedaan-
perbedaan di antara kategori budaya yang spesifik. Pertanyaan-pertanyaan
yang disusun adalah pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan menemukan
kotras, seperti, “Apa yang membuat berbeda antara politik nilai dan
politik kekuasaan?” atau pertanyaan-pertanyaan untuk menggali makna-
makna budaya yang lebih dalam.
41
Informan utama wawancara formal ini adalah pendiri MCW yang
sampai sekarang masih aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan MCW dan
dua relawan MCW yang dalam perkembangannya diangkat menjadi badan
pekerja MCW. Informan selanjutnya adalah relawan yang bergabung saat
penulis melakukan penelitian di MCW. Yang pertama dipilih karena ialah
sumber ide dan pewaris budaya di MCW. Yang kedua dipilih untuk
meninjau apakah persepsi yang penulis simpulkan dari pengamatan
dilakukan juga dialami oleh mereka.
c. Dokumentasi
Untuk mendukung pengamatan peneliti dan wawancara, digunakan
juga studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan MCW (misalnya Standard Operating Procedure, brosur, tulisan, dan
buku-buku yang menulis mengenai MCW).
3.6. Keabsahan Data
Penelitian partisipatif-aktif seperti yang dilakukan penulis, memiliki
keunggulan keabsahan data karena peneliti terlibat langsung dengan situasi sosial
yang diteliti dan menjadi bagian di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh
Neuman (2007:120), peneliti kualitatif lebih menekankan otensitas daripada
validitas. Artinya, penelitian ini mencoba memberikan interpretasi yang adil,
jujur, dan seimbang dari kehidupan sosial dari sudut pandang orang yang hidup di
42
dalamnya setiap hari. Dengan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari
situasi sosial yang diteliti, peneliti bisa menggambarkan apa yang terjadi
sesungguhnya dalam situasi sosial tersebut.
3.7. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis Spradley
(1980), terdiri dari membuat analisis domain, membuat taksomonis, membuat
komponensial, dan menemukan tema budaya.
(1) Membuat analisis domain
Domain budaya adalah kategori dari makna-makna budaya yang
mencakup kategori lebih kecil lainnya. Ada tiga elemen dasar dalam domain
budaya, yaitu cover term (Y), included term (X), dan semantic relationship.
Cover term adalah nama dari sebuah domain budaya, misalnya relawan.
Included term adalah nama-nama dari kategori yang lebih kecil dari cover
term. Misalnya, relawan tetap, relawan tidak tetap, dan relawan pupuk
bawang.13 Elemen yang ketiga adalah single semantic relationship, yaitu
hubungan antara dua kategori di atas. Dalam contoh istilah relawan di atas,
hubungan semantiknya adalah “jenis relawan”. Sehingga, dapat dikatakan:
“relawan tetap (adalah jenis dari) relawan.” Domain budaya sangat banyak
dan bisa dikategorikan menjadi sembilan macam, berdasarkan hubungan
semantiknya, yaitu: strict inclusion (X adalah jenis dari Y), spatial (X adalah 13 Pupuk bawang adalah istilah Jawa yang artinya “ketegori khusus”, biasanya dianggap sebagai pihak yang mendapat perlakuan khusus, tidak mendapat ekspektasi seawajarnya. Ia diberi ekspektasi yang kurang karena dianggap tidak mampu .
43
bagian dari Y), cause-effect (X adalah hasil/result dari Y), rationale (X adalah
alasan dari melakukan Y), location for action (X adalah tempat untuk
melakukan Y), function (X digunakan untuk Y), means-end (X adalah cara
untuk melakukan Y), sequence (X adalah langkah untuk Y), dan attribution
(X adalah karakteristik dari Y). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
strict inclusion untuk gambaran umum MCW, di mana penulis
mendeskripsikan lokasi, aktor, dan aktivitas di MCW. Strict inclusion, yang
merupakan kategori domain budaya mengenai macam-macam hal tertentu,
dipilih karena hal itu merupakan cara yang sederhana untuk menggambarkan
MCW secara umum.
(2) Membuat analisis taksonomi
Taksonomi adalah serangkaian kategori yang diorganisasi dari sebuah
domain budaya. Ia lebih detail, lebih terperenci, dan lebih terpecah lagi
daripada domain budaya. Analisis taksonomi ini dilakukan selama observasi
terfokus dilakukan.
(3) Membuat analisis komponensial
Analisis komponensial adalah pencarian sistematis untuk komponen-
komponen makna yang terlekat pada kategori-kategori budaya. Setiap seorang
peneliti menemukan kontras atau perbedaan di antara komponen-komponen
anggota domain budaya, kontras-kontras ini bisa dilihat sebagai atribut atau
komponen makna. Atribut-atribut makna ini dapat digambarkan di dalam
44
“tabel paradigma”. Misalnya, analisis komponensial dilakukan terhadap
kategori budaya jenis relawan:
Tabel 3. Contoh Tabel Paradigma
Domain Dimension of Contrast
Siapa yg melakukan Beradab? Tujuan Posisi
Kekuasaan Politik Nilai “Kita”
(Aktivis NGO)
Ya Kemanusiaan/Kebajikan Sebagai Instrumen
Politik Kekuasaan
“Mereka (Politikus Praktis)
Tidak Kekuasaan Semata Sebagai Tujuan
Sumber: analisis pribadi
Dari kontras di atas, misalnya, dapat diketahui bahwa atribut budaya
yang melekat dalam dimensi kontras di atas adala kebajikan.
(4) Menemukan tema budaya
Tema budaya adalah “sebuah postulat atau posisi, baik itu
dideklarasikan atau hanya terkandung secara implisit, dan biasanya
memandu perilaku atau menstimulasi aktivitas, yang secara tidak terlihat
diterima atau secara terbuka dipromosikan di dalam sebuah masyarakat”
(Opler dalam Spradley, 1980:140).
Inilah yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan “Budaya apa yang
dimiliki oleh komunitas A?” Sedangkan pertanyaan “Bagaimana Y
dilakukan?” sudah dapat dijawab melalui analisis domain, taksonomi, dan
komponensial terhadap hubungan semantik “X adalah langkah dalam
melakukan Y”.
45
Dalam usaha menemukan tema budaya, digunakan dua strategi.
Pertama, dengan membenamkan diri dalam segala hasil observasi sampai
menemukan tema budaya. Kedua, melakukan analisis komponensial terhadap
domain budaya atau cover terms.
Tema budaya juga dapat ditemukan dengan melihatnya dari
perspektif teori yang ada, dalam hal ini teori Pierre Bourdieu tentang
reproduksi budaya dan reproduksi sosial.
3.8. Posisi Penulis di Malang Corruption Watch
Keterlibatan penulis dengan MCW dimulai sejak melakukan PKN
(Praktek Kerja Nyata). Saat itu, Badan Pekerja MCW praktis hanya dua orang,
yaitu Zia Ulhaq sebagai koordinator dan Muhammad Didit Sholeh (Didit) sebagai
wakil koordinator.
Pertengahan September 2011 penulis menghubungi Zia Ulhaq, koordinator
MCW saat itu, via pesan singkat (SMS). Kemudian, ia menyuruh penulis ke
kantor untuk menemui Didit dan menyerahkan surat permohonan PKN. Penulis
bertemu dengan Didit satu kali untuk berbincang. Hasil pembicaraan itu adalah
disetujuinya permohonan PKN dan penulis diundang untuk datang ke rapat
penyusunan program tiga bulan MCW. Rapat itu ternyata tertunda dua minggu
dan baru dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011, dan dihitung sebagai hari pertama
pelaksanaan PKN.
Kehadiran satu orang yang bisa memberikan waktu yang penuh tentu
sangat dibutuhkan oleh MCW saat itu. Penulis kemudian terlibat di hampir semua
46
kegiatan MCW, bahkan kemudian diserahi tanggung jawab untuk membantu Didit
melaksanakan open recruitmen relawan MCW. Setelah program PKN berjalan
selama hampir satu bulan, penulis diajak berbincang dengan Dewan Pengurus
Yayasa, dipimpin oleh LJK. Ia meminta penulis untuk bergabung menjadi badan
pekerja. Sebelum pertemuan itu, secara informal Didit beberapa kali meminta
penulis untuk memberikan tenaga dan waktu yang banyak untuk membantu dia
melaksanakan tugas-tugas di MCW. Ajakan yang informal dan formal itu penulis
setujui dan mulai saat itu penulis bergabung menjadi anggota aktif atau badan
pekerja MCW sebagai koordinator bagian informasi dan dokumentasi (indok).
Setelah itu, diadakan in-house training untuk percepatan kesiapan penulis sebagai
badan pekerja. Ada dua orang lain yang juga ikut, mereka adalah relawan hasil
perekrutan tahun lalu yang diminta kembali aktif setelah lama vakum.
Setelah melakukan open recruitmen pada bulan Oktober-November 2011,
MCW mendapatkan tenaga baru. Ini agak melegakan karena satu orang yang ikut
in-house training bersama penulis kembali vakum lagi.14 Seperti yang sudah
dijelaskan di atas, open recruitmen kali ini menghasilkan 4 orang yang bertahan
aktif di MCW.
Pada Raker MCW tanggal 24-25 Januari 2011, penulis terpilih sebagai
wakil koordinator badan pekerja, mendampingi Didit yang saat itu terpilih sebagai
koordinator badan pekerja. Setelah raker, berjalanlah beberapa kegiatan MCW.
Saat itu, Rahim dilihat lebih mampu menjalankan fungsi koordinasi lapangan,
14 Datang-perginya relawan di MCW menjadi hal yang biasa karena memang tidak ada perjanjian yang ketat mengenai masa kerja. LJK lebih menyebut perjanjian itu sebagai “komitmen moral”. Artinya, dipenuhinya janji seorang relawan untuk memberi waktu diMCW adalah hal moral sehingga tidak ada sanksi secara spesifik, hanya sanksi sosial.
47
terutama advokasi dibanding penulis. Pada saat itu penulis juga sedang fokus
mengerjakan proposal penelitian skripsi sehingga waktu di MCW agak berkurang.
Lalu, pada suatu pertemuan LJK menawarkan ide untuk membagi posisi wakil
koordinator menjadi dua, yaitu wakil koordinator internal-program, yang
bertanggung jawab membantu relawan mendesain program, mengurusi perjanjian
kerjasama dengan pihak luar, dan memastikan pengerjaan administrasi program
(misalnya laporan dan perencanaan) dikerjakan dengan baik, dan membantu
peningkatan kapasitas relawan; dan wakil koordinator eksternal-advokasi, yang
bertanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan berjalan di lapangan,
termasuk kegiatan advokasi. Wakil koordinator internal-program dijabat penulis
sedangkan wakil koordinator eksternal-advokasi dijabat oleh Rahim.
Bersama Didit, Ayu, dan Rahim, penulis termasuk salah satu orang yang
dianggap sebagai “pilar MCW”. Ini berimplikasi pada cukup besarnya pengaruh
penulis dalam keputusan-keputusan MCW, terutama dalam hal pemikiriran
(ide)—mengingat dari segi umur, penulis salah satu yang senior di MCW di
antara relawan atau badan pekerja yang lain, seperti yang ternyata dalam
ungkapan LJK, “Jadi gimana Gadi, kamu bisa di sini sampai kapan? Kami masih
butuh otakmu di sini.”15
Posisi penulis yang sudah menjadi bagian MCW memberikan kemudahan
untuk menggali data. Seperti yang sudah diungkapkan dalam Bab II, penulis tidak
perlu melakukan banyak wawancara formal dengan aktor yang ada di MCW.
Perbincangan-perbincangan informal menjadi sarana untuk menggali apa yang
15 Rapat bulan Maret 2011.
48
ada di dalam pikiran anggota MCW. Kalimat-kalimat spontan yang keluar saat
berkegiatan atau sekedar duduk santai bersama juga digunakan sebagai data dalam
penelitian ini. Kondisi ini juga memberikan kadar naturalitas yang tinggi bagi data
yang diperoleh.
Namun, selain memberikan kemudahan penggalian data dan kadar
naturalitas yang tinggi, timbul pula pertanyaan mengenai subyektifitas penulis
dalam penelitian ini. Subyektifitas itu diatasi dengan memaparkan hasil
pengamatan dan kalimat-kalimat yang direkam apa adanya lebih dahulu.
Kalaupun ada penilaian pada pemaparan data, itu hanya bersifat analisis yang
obyektif, misalnya pernyataan bahwa porsi aktivitas di MCW yang paling besar
adalah aktivitas advokasi. Penilaian yang lebih dalam dilakukan dengan analisis
komponensial Spradley yang kemudian ditinjau secara teoritis menggunakan
pemikiran Pierre Bourdieu sehingga penilaian yang diberikan adalah penilaian
yang mempunyai landasan teori dan metode penelitian, bukan sekedar persepsi
penulis.
49
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum
Dalam bagian ini, dijelaskan seluk beluk organisasi Malang Corruption
Watch dan situasi sosialnya supaya pembaca tidak asing dengan situasi sosial
yang menjadi subyek penelitian penulis. Di dalamnya termasuk hasil descriptive
observation yang mencakup penjabaran aktor, aktivitas, dan lokasi geografis
tempat yang diteliti (lihat Bab III, Proses Pengumpulan Data). Setelah itu, akan
dijelaskan juga bagaimana penulis bergabung menjadi anggota aktif Malang
Corruption Watch dan bagaimana peran penulis dalam organisasi tersebut.
4.1.1. Profil Malang Corruption Watch
Malang Corruption Watch adalah salah satu organisasi non-pemerintah
atau non-goverment organization (NGO) yang bekerja memantau korupsi,
dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2000; terinspirasi oleh pendirian Indonesia
Corruption Watch (ICW). Cakupan kerja MCW adalah Malang Raya (Kota
Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang).
Ide mendirikan MCW bermula dari komunitas diskusi para aktivis, yaitu
aktivis mahasiswa, mantan aktivis mahasiswa dan beberapa dosen yang
mempunyai kepedulian pada pemantauan kebijakan publik di Malang Raya.
Komunitas diskusi ini mulai sebelum reformasi 1998. Pada akhir tahun 1999,
50
komunitas ini mulai memfokuskan diskusinya pada agenda-agenda pemantauan
dan pemberantasan korupsi.
Dilihat dari definisi tugasnya, yaitu melakukan pemantauan kasus korupsi
di pemerintahan, organisasi ini bisa diketagorikan sebagai organisasi watchdog,
yaitu organisasi yang memilih peran oposan terhadap pemerintah; bekerja
memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya,
MCW juga menjalankan fungsi-fungsi advokasi, misalnya melakukan
pendampingan terhadap Pedagang Pasar Dinoyo dan Blimbing yang akan
direlokasi karena lokasi berdagang mereka yang akan dijadikan mall dan
apartemen—fungsi yang lebih tepat dijalankan oleh LBH.16 Pengambilan peran
ini dapat dimaklumi mengingat kantor perwakilan LBH Surabaya yang ada di
Malang kekurangan orang.
Pada tanggal 24-25 Januari 2011 MCW melakukan rapat kerja tahunan
untuk menyepakati program strategis selama tiga tahun ke depan. Rapat itu
kemudian menyepakati bahwa MCW tetap menjalankan visinya yang awal, yaitu
“Terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan
berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi
dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.” Visi ini kemudian
dijewantahkan dalam program strategis selama tiga tahun, yaitu (1) melakukan
monitoring, investigasi, dan advokasi kasus-kasus korupsi di sektor pelayanan
publik, hukum-peradilan, dan politik (2) melakukan pencegahan korupsi melalui
pendidikan publik dan penguatan jaringan untuk membentuk zona-zona anti- 16 Lembaga Bantuan Hukum; yayasan yang didirikan Adnan Buyung Nasution yang definisi perannya adalah mendampingi pihak-pihak rentan yang menjadi korban kebijakan struktural pemerintah yang tidak memihak pihak rentan tersebut.
51
korupsi di sektor pelayanan publik, hukum-peradilan, dan politik (3) membangun
kemandirian lembaga dan menggalang dukungan masyarakat melalui public fund-
raising. Yang terakhir ini mencoba meniru apa yang telah dilakukan oleh
Greenpeace dalam menggalang dana, yaitu dengan memberi kesempatan pada
pendukung-pendukungnya untuk memberikan dana melalui auto-debet,17 dan
kartu kredit. Public fund-raising ini dilakukan dengan bekerjasama dengan
Indonesia Corruption Watch.
Sesuai dengan program strategisnya, kerja-kerja MCW dibagi ke dalam
divisi-divisi, yaitu (1) Divisi Pelayanan Publik, yang melakukan kerja-kerja
monitoring, investigasi, dan advokasi di sektor pelayanan publik; (2) Divisi
Hukum dan Peradilan, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga
hukum dan peradilan; (3) Divisi Korupsi Politik, yang melakukan monitoring di
sektor politik; dan (4) Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi, yang
mendukung ketiga divisi di atas dalam mencari, mendokumentasi, menganalisis,
dan mempublikasi data-data yang berkaitan dengan kasus korupsi di Malang
Raya. Masing-masing divisi dikepalai satu orang yang membawahi kelompok
kerja relawan.
Untuk koordinasi di tingkat top management, MCW dipimpin oleh
seorang koordinator yang dibantu dua wakil koordinator, yaitu wakil koordinator
bagian internal—bertanggung jawab untuk mendesain program bersama kepala
divisi, memastikan lengkapnya laporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,
bertanggung jawab atas rekrutmen relawan, dan kerjasama dengan pihak luar; dan
17 Pemotongan langsung rekening tiap bulan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati
52
wakil koordinator eksternal—bertanggung jawab untuk memastikan semua
program berjalan di lapangan dan bertanggung jawab mengkoordinir setiap
kegiatan advokasi.
Model koordinasi di atas ditetapkan sekitar bulan April, setelah melihat
adanya kebutuhan 2 orang wakil koordinator. Sebelumnya koordinator hanya
dibantu oleh seorang wakil koordinator; yang ternyata ditemukan berat dikerjakan
oleh satu orang. Selanjutnya struktur organisasi yang sudah dideskripsikan di atas
ditampilkan dalam bagan berikut:
53
Bagan 2. Struktur Organisasi MCW18
Sumber: MCW
4.1.2. Aktor-aktor Malang Corruption Watch
Sebelum rapat kerja bulan Januari 2011, badan hukum MCW berbentuk
yayasan. Pada saat rapat kerja, disepakati bahwa badan hukum MCW akan
18 Dalam bagan ini, struktur di atas badan pekerja tidak dimasukkan karena belum ada keputusan yang jelas dalam diri MCW mengenai struktur yang baru setelah mereka memutuskan mengubah badan hukum menjadi perkumpulan. Namun, seperti yang akan dijelaskan, orang-orang yang dahulu menjadi pengurus yayasan sebagian besar akan menjadi pengurus perkumpulan.
Relawan (Kelompok Kerja) Riza A., Muh. Hafi, Yunita Dwi L., C. Lutfi, Ahmad Anggoro,
Defri Aries S.
Bagian Informasi, Dokumentasi, dan
Publikasi Ruchul Jannah,
Rusdiyanto Rusdiyanto
Bagian Monitoring
Korupsi Politik
Umarul Faruk
Bagian Monitoring Hukum dan Pelayanan
Publik Abdul Hakim
Wakil Koordinator
Internal Gadi K. Makitan
Wakil Koordinator
Eksternal Abdur Rahim
Koordinator Badan Pekerja
Moh. Didit Sholeh
Administrasi dan
Keuangan Ayu A. Satya
54
berganti menjadi perkumpulan dengan alasan bahwa organisasi berbadan hukum
yayasan beresiko diambil asetnya oleh pemerintah saat dibubarkan. Namun,
sampai tulisan ini dibuat, belum ada langkah konkret untuk merealisasikan
penggantian itu. Yang dilakukan adalah mendata kembali nama-nama yang akan
dijadikan pengurus perkumpulan. Hal ini dilakukan untuk memperluas jaringan
MCW, seperti yang dikatakan Luthfi J. Kurniawan, “Nggak papa pengurus
yayasannya kita gemukin, biar jaringan kita luas,”19
Untuk memudahkan, penulis akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di
MCW dengan tetap menggunakan struktur kepengurusan yayasan, yang
mengikuti Undang-Undang No 28 Tahun 2007, dengan komponen (1) Dewan
Etik/Pembina sebagai lembaga yang memberikan penilaian kinerja pengurus, (2)
Dewan Pengurus Yayasan sebagai penanggung jawab operasionalisasi organisasi
yayasan MCW, (3) Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan
kinerja terhadap dewan pengurus dan badan pekerja, dan (4) Badan Pekerja
sebagai pelaksana program yayasan MCW.
Dewan Etik/Pembina sampai saat ini masih dijabat satu orang, yaitu Prof.
Mukhtie Fajar. Ia adalah orang yang sangat disegani di MCW. Segala keputusan
penting yang berkaitan dengan keberlangsungan lembaga akan dibawa kepadanya
untuk dimintai pendapat dan persetujuan; salah satunya adalah perubahan badan
hukum MCW. Prof. Mukhtie Fajar, yang sekarang adalah rektor Universitas
Widyagama Malang dan mantan Wakil Mahkamah Konstitusi, adalah “nama
besar” yang memayungi MCW.
19 Dikatakan saat rapat pengurus, 28 Januari 2011.
55
Dewan Pengurus Yayasan dipimpin oleh Luthfi J. Kurniawan (LJK;
dipanggil Mas Luthfi oleh relawan), sarjana sosial alumnus Universitas
Muhammadiyah Malang, mantan aktivis ’98, pria berumur sekitar empat puluh
tahun, etnis Madura. Ia adalah satu-satunya pendiri MCW yang sampai sekarang
masih bertahan menjadi aktivis MCW. Menjabat sebagai koordinator MCW
selama 3 periode, sebelum menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Sekarang
ia juga berprofesi sebagai dosen FISIP UMM. Dalam perspektif Pierre Bourdieu,
ia adalah aktor dengan PAu (Pedagogic Authority). Dari pembicaraan-
pembicaraan spontan orang-orang yang penulis temui yang merupakan mantan
aktivis MCW, wartawan, dan aktivis MCW sendiri, penulis mendapatkan kesan
bahwa ia merupakan representasi dari aktivis watchdog kota Malang, karena
dianggap sebagai orang yang konsisten berjuang di garis depan civil society
dengan track record yang bersih (bebas dari kongkalingkong kekuasaan dengan
pemerintah). Penulis mengamati dan mengalami bahwa ia jugalah yang menjadi
pemandu moral (yang memberikan batasan-batasan norma perilaku) MCW. Ia
yang banyak melakukan praktek imposisi budaya kepada aktivis MCW yang lain.
Zia Ulhaq (dipanggil Mas Zia) adalah koordinator MCW setelah Luthfi. Ia
menjabat selama 1 periode, dari tahun 2009 hingga 2011. Raker bulan Januari
adalah momen penyerahan jabatannya kepada koordinator yang berikutnya. Zia
adalah mantan mahasiswa Luthfi, yang kemudian dikader menjadi koordinator
MCW. Setelah lulus dari S1, ia melanjutkan program S2 Administrasi
Pemerintahan di Universitas Brawjiaya. Jika Luthfi adalah representasi, Zia sering
menjadi contoh tentang ‘apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh aktivis’. Ia
56
tidak melakukan korupsi atau kejahatan apa pun, tetapi habitus-nya sering
dijadikan contoh habitus yang tidak sesuai dengan ideal aktivis civil society
misalnya, mengambil peran dan kemunculan publik yang dominan sehingga
relawan lain menjadi tenggelam, sampai kepada trivia-trivia seperti terlambatan
datang dan tidak menepati janji. Dan, walaupun tidak langsung, digambarkan
sebagai orang yang opurtunis.20 Hal ini penulis lihat sebagai gambaran mental
yang satu di dalam diri aktivis MCW angkatan tahun 2009 ke atas.
Dewan pengurus yayasan yang lain, yaitu Hesti Puspitosari (Mbak Hesti),
Khalikusabbir (Mas Sabbir) dan Muhammad Rusdi (Mas Rusdi), adalah mantan
badan pekerja MCW yang seangkatan dengan Zia Ulhaq. Sekarang, mereka
adalah karyawan di In-TRANS Publishing, unit usaha penerbitan yang didirikan
Luthfi dan kawan-kawan untuk membiayai kegiatan MCW dan menghidupi para
aktivisnya. Mereka ini, walau tidak dalam struktur kepengurusan eksekutif, tetap
bersentuhan dengan aktivitas-aktivitas MCW tetapi tidak dalam posisi pengambil
keputusan.
Orang-orang di atas rata-rata berumur tiga puluh tahunan, jauh dari usia
Badan Pekerja yang semuanya diisi oleh mahasiswa yang belum lulus dari
universitas. Koordinator MCW adalah Muhammad Didit Sholeh (Didit),
mahasiswa FKIP Universitas Islam Malang angkatan 2007, etnis Bali. Sebagai
alumni pesantren, ia adalah seorang yang taat beragama dan memiliki
pengetahuan yang cukup mendalam tentang agamanya (Islam). Pandangan-
20 Istilah opurtunis di sini adalah kesimpulan penulis sendiri, untuk menunjuk pada ciri perilaku yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan organisasi, atau lebih luas, kepentingan “publik” (menurut penilaian dan definisi dari anggota MCW sendiri, terutama aktor dengan PAu)
57
pandangan politiknya ditentukan selain dari agamanya juga dari pemikiran-
pemikiran filsafat politik sekuler yang pernah ia baca, seperti milik Kant, Hegel,
dan Montesqieu, seperti halnya juga pemikiran-pemikiran sosial seperti milik
Marx dan Gramsci. Ia juga adalah mantan aktivis Perjuangan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII). Ia telah bekerja bersama Zia selama kurang lebih satu tahun
sebelum menjadi pengganti Zia.
Wakil koordinator eksternal sekaligus koordinator Divisi Pelayanan Publik
adalah Abdur Rahim (Rahim), mahasiswa Fakultas Humaniora Universitas Islam
Negeri Malang angkatan 2008, etnis Madura. Sebagai aktivis PMII
pemahamannya tentang Islam dan politik juga kuat. Ia termasuk dalam golongan
yang moderat, diketahui saat penulis melakukan perbicangan dengannya dan
menemukan pandangannya yang menyebutkan bahwa dakwah adalah membiarkan
seseorang memilih dan menjalani apa yang ia yakini.21
Urusan kesekretariatan dan keuangan ditangani oleh Ayu Andarini S.
(Ayu). Ia adalah mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas Muhammadiyah
Malang angkatan 2008. Keturunan Jawa tapi lama tinggal di Aceh. Pengurus
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang. Seorang Muslim yang taat,
terlihat dari pakaian yang digunakannya, yang menutup setiap bagian tubuhnya
dan pemikiran-pemikiran yang hampir selalu mengacu pada ke-Islaman.
Semua badan pekerja yang telah disebut di atas sering disebut pilar MCW
oleh LJK. Penulis mengamati itu dikarenakan kapasitas kepemimpinan dan
intelektual mereka (mengingat masing-masing adalah aktivis mahasiswa yang
21 Perbincangan tanggal bulan April 2011 (tanggal tidak tercatat)
58
sudah dalam tataran senior), selain juga karena komitmen waktu yang lebih
dibanding teman-teman yang lain.
Koordinator Divisi Korupsi Politik adalah Umarul Faruk, mahasiswa
FISIP Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008, etnis Madura. Ia
bergabung dengan MCW sejak perekrutan relawan bulan November 2010.
Kapasitas intelektual, kepemimpinan, dan komitmen waktunya jugalah yang
membuat ia diangkat sebagai koordinator Divisi Korupsi Politik. Sedangkan
Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan dijabat oleh Muhammad Hafi,
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, angkatan 2008.
Keturunan Sunda. Namun, dalam kurun waktu April-Juni, ia kurang aktif di
MCW.
Satu-satunya relawan yang berstatus badan pekerja tetapi tidak menjabat
koordinator adalah Defri Aries Sandi, mahasiswa FISIP Universitas
Muhammadiyah Malang angkatan 2008. Ia sampai sekarang adalah mahasiswa
LJK di jurusan Kesejahteraan Sosial. Ketertarikannya yang minim terhadap
pemikiran sosial-politik (ia lebih tertarik pada dunia bisnis) membuatnya
diletakkan dalam posisi yang tidak krusial. Ia bergabung karena perasaan sungkan
dan hormat terhadap dosennya. Namun, pada bulan Juli ia memutuskan untuk
tidak menjadi badan pekerja lagi dan menyandang status sebagai relawan.
Selain badan pekerja di atas, pada bulan Maret MCW mengadakan
perekrutan relawan baru. Dari tiga puluh empat orang yang mendaftar, ada empat
orang yang sampai sekarang masih aktif, yaitu Chairul Lutfi (Lutfi), Ruchul
Jannah (Uni), Abdul Hakim (Hakim), Rusdiyanto (Rusdi), Riza Amalia (Riza)
59
dan Akhmad Anggoro (Yoyon). Mereka semua adalah mahasiswa Universitas
Islam Negeri Malang. Lutfi (jurusan Syariah) dan Yoyok (Teknik Informatika)
adalah mahasiswa angkatan 2010. Rusdi (Ilmu Pendidikan) dan Riza (Psikologi)
adalah mahasiswa angkatan 2009. Hakim adalah mahasiswa angkatan 2008
jurusan Syariah, sedangkan Uni adalah mahasiswa Sastra Inggris angkatan 2007.
Uni yang tertua dari semua relawan baru. Dan, karena komitmennya yang tinggi
pada MCW (terlihat dari hasil kerja dan presentase waktunya di MCW) ia
diangkat sebagai badan pekerja di Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi,
menggantikan Suhardi yang mengundurkan diri pada bulan April.
Sebagai Dewan Pengawas, penulis mengamati ada dua orang yang aktif
membantu. Pertama, Zulkarnaen, M.H (Mas Zul). Ia adalah dosen Fakultas
Hukum Universitas Widyagama Malang. Dahulu adalah aktivis MCW, satu
angkatan dengan LJK. Yang kedua adalah Setyo Eko Cahyono, S.H. (Mas Eko).
Ia adalah mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum. Sekarang berprofesi sebagai
advokat. Ia banyak membantu MCW dalam hal membuat opini hukum. Yang
terakhir ada seorang bernama Mustafa Lutfi, M.H (Mas Mustafa). Ia adalah
seorang penulis, yang bukunya sering diterbitkan oleh In-TRANS Publishing. Ia
berencana dimasukkan ke dalam Dewan Pengawas, namun belum ada surat
keputusannya. Dalam kegiatan diskusi atau pun rapat penggalian dana melalui
penerbitan jurnal, ia sering membantu.
60
4.1.3. Aktivitas-aktivitas Malang Corruption Watch
a. Rapat
Rapat rutin diadakan setiap hari Jumat Pk. 13.00 WIB. Rapat ini
membahas program-program yang sedang dijalankan, mengontrol pekerjaan-
pekerjaan setiap minggu yang sudah direncanakan, dan mengevaluasi kegiatan
yang sudah dilaksanakan.
Dalam rapat-rapat rutin, relawan juga dilibatkan untuk berpikir bersama.
Mereka berhak memberikan pendapat tentang permasalahan yang sedang
dibicarakan atau menyelesaikan suatu masalah secara bersama.
Penulis mengamati bahwa rapat juga adalah sarana pengimposisian budaya
dari LJK kepada aktivis yang masih muda.22 Alasan-alasan mengapa sebuah
kegiatan dilakukan dan sebuah keputusan diambil dikemukakan saat rapat. LJK
juga sering memberi panduan filosofi kepada para relawan. Seperti etika-etika
kerja di MCW dan mengapa MCW ketat tidak ingin menerima dana dari lembaga
pemerintahan, yaitu karena ingin mempertahankan independensi. Juga mengenai
mengapa pemerintah harus dilawan dan dirong-rong terus. Juga menganai
mengapa yang harus dibantu adalah pihak yang rentan, bahwa karena nilai yang
dipegang adalah masyarakat yang adil dan beradab.
b. Advokasi
Advokasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha mempengaruhi
dan atau mengubah kebijakan yang telah dibuat atau direncakan pemerintah
22 LJK sering terlibat dalam rapat-rapat badan pekerja, walaupun tidak selalu.
61
karena dianggap merugikan satu atau beberapa pihak dan bertentangan dengan
prinsip keadilan sosial yang dianut MCW, baik itu berupa kegiatan pendampingan
kepada masyarakat yang meminta pertolongan atau atas inisiatif MCW sendiri.
Kegiatan advokasi ini—menurut pengamatan penulis—banyak menyita waktu
aktivis MCW dan bahkan membuat pekerjaan di MCW overload (kelebihan
beban) sehingga pekerjaan-pekerjaan rutin yang bersifat adminstratif sering
terbengkalai. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan lain, seperti laporan riset dan
laporan program yang selesai hampir selalu melewati tenggat waktu. Saat penulis
mengatakan ini dalam rapat, LJK pernah berkata, “Masa kamu tega membiarkan
orang yang minta tolong,”23 Pemikiran seperti inilah yang menjadikan advokasi
menjadi kegiatan yang menempati tempat teratas dalam urutan prioritas di MCW,
disadari atau tidak. Siapa pun akan terlibat dalam kegiatan advokasi karena beban
kerja dan jumlah tenaga yang tidak seimbang.
Kegiatan advokasi yang dilakukan MCW selama penulis terlibat di
dalamnya adalah mendampingi Pedagang Pasar Dinoyo dan Blimbing untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah yang ingin mendirikan mall dan apartemen
di kedua pasar tersebut. Advokasi dimulai dengan menyusun tim kerja, bertemu
dengan pedagang pasar untuk mendiskusikan langkah-langkah advokasi, dan
selanjutnya mendampingi para pedagang dalam setiap usaha yang mereka lakukan
(hearing, demonstrasi, dan sebagainya).
Selain mendampingi Pedagang Pasar Dinoyo dan Blimbing, MCW juga
membantu mengadvokasi kasus-kasus di bidang pendidikan. Advokasi di bidang
23 Rapat koordinasi rutin hari Jumat, 4 Februari 2011.
62
pendidikan ini sebenarnya diinisasi oleh beberapa orang aktivis pendidikan yang
menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Pendidikan. Dalam hal ini, MCW
berperan sebagai penyokong; menjadi tempat berkonsultasi para aktivis tersebut.
Pada masa kepemimpinan Zia, ada satu kasus sengketa tanah yang
diadvokasi MCW. Yang menangani saat itu adalah Zia dan Rahim. Namun,
belakangan diketahui bahwa kasus itu sebenarnya sengketa pribadi, sehingga
diputuskan MCW lepas tangan.
c. Riset
Riset yang dimaksud di sini adalah kegiatan mengamati,
mendokumentasikan fakta-fakta berkaitan dengan korupsi atau pelayanan publik,
dan menyusun analisis. Kegiatan riset atau penelitian ini secara esensial hampir
sama dengan yang dilakukan di perguruan tinggi tapi dengan standar yang
berbeda. Dikatakan standar yang berbeda bahwa riset ini tidak dimaksudkan untuk
akumulasi pengetahuan yang berimplikasi pada pembacaan teori yang mendalam
dan model penulisan yang diikat dengan model tertentu. Riset yang dilakukan
MCW lebih kepada usaha menggali pengetahuan untuk melakukan tekanan-
tekanan tertentu kepada pemerintah.
Salah satu contoh adalah survey pengetahuan dan pengalaman masyarakat
terhadap layanan badan publik. Survey itu menunjukkan bahwa 65 % responden
menyatakan bahwa pelayanan publik di kota Malang tidak memuaskan. Data ini
kemudian digunakan untuk mengadakan forum dengan pejabat publik (kepala-
63
kepala dinas), LSM, dan akademisi untuk mendorong adanya pelayanan publik
yang lebih baik lagi.
Yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya data itu belum lengkap. Dari
seribu kuisioner yang disebar, hanya 250 saja yang dianalisis karena keterbatasan
waktu (satu zona, di antara 5 pembagian zona kota Malang).24 Namun, beginilah
aturan LSM watchdog ini bekerja. Kedalaman data tidak terlalu penting
dibandingkan dengan momen kapan data itu bisa digunakan untuk menekan
pemerintah. Ketepatan momen menjadi prioritas utama. Berkejaran dengan waktu
telah menjadi hal yang sangat biasa.
Begitu juga dengan riset pendataan kasus korupsi di Jawa Timur. Riset
yang berjudul Kasus Korupsi dan Kinerja Kejaksaan Tahun 2010 ini bertujuan
untuk memetakan modus, aktor, kerugian negara akibat korupsi di wilayah Jawa
Timur, dan kinerja kejaksaan di wilayah Jawa Timur dalam menangani dugaan
kasus korupsi.
Riset ini dilakukan dengan metode media review. Media review yang
dimaksud di sini adalah mencari data-data kasus korupsi melalui pemberitaan
media. Tahun lalu, riset ini dilakukan dengan mengkliping koran. Namun, karena
tahun ini riset baru dilakukan di pertengahan tahun, pengambilan data dilakukan
dengan cara googling.
Dalam perencanaan, kegiatannya meliputi: (1) input data, yaitu mengisi
tabel data kasus korupsi dari hasil googling; (2) crosscheck data, yaitu melakukan
pengecekan silang dalam suatu waktu bersama untuk melihat kebenaran data yang
24 Zona itu terbagi atas zona utara, zona selatan, zona barat, dan zona timur
64
telah masuk; (3) analisis data; (4) validasi data dari teman-teman jaringan, yaitu
mengundang jaringan Malang Corruption Watch di seluruh Jawa Timur untuk
memberi tambahan data atau mengoreksi data; (5) publikasi hasil riset kepada
media.
Namun, juga karena keterbatasan waktu dan tidak hadirnya pada undangan
dalam pertemuan jaringan untuk memberi dan mengoreksi data kegiatan,
crosscheck data tidak dilakukan. Tapi pada akhirnya pun data tetap
dipublikasikan, baik di koran maupun melalui radio. Acara laporan akhir tahun
MCW kepada publik pada bulan Desember dijadikan momen untuk
mempublikasikan data, yang tujuannya kembali untuk menekan pemerintah
supaya lebih bersih lagi. Dalam publikasinya di media pun, MCW tidak
menekankan metode pencarian data ini, yaitu melalui googling. Ini berbeda
dengan ranah akademis yang sangat menekankan metode supaya data itu bisa
dinilai validitasnya.
d. Mengantar undangan
Kegiatan yang sering dilakukan oleh aktivis MCW (terutama yang junior)
adalah mengantarkan undangan acara yang diadakan MCW. Kegiatan ini memang
ditujukan untuk menghemat anggaran. Namun penulis mengamati ada fungsi laten
di baliknya. Kegiatan ini membuat relawan MCW familiar dengan perkantoran
pemerintah di kota Malang. Dan, kegiatan mengundang—yang sering didahului
menelepon yang diundang—juga menjadi sarana untuk relawan MCW dikenal
dan mengenal jaringan MCW.
65
e. Berbincang
Berbincang biasanya dilakukan setelah rapat selesai, setelah melakukan
kegiatan dan di awal hari sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis.
Biasanya, ini terjadi secara spontan setelah melihat pemberitaan di koran atau
adanya kasus baru yang dilaporkan atau menanggapi masalah yang sedang terjadi
di atau menyangkut badan pekerja.
Dalam kegiatan perbincangan spontan inilah LJK sering membagikan
pengalaman-pengalaman pribadinya yang berhubungan dengan bekerja bagi
masyarakat, pemikiran-pemikiran mengenai idealisme perjuangan masyarakat
sipil, dan dorongan untuk bertahan tetap mengerjakan visi sekalipun dalam situasi
yang sulit. LJK juga bertindak sebagai polisi moral bagi aktivis MCW. Ia sering
memberi penilaian terhadap perilaku-perilaku politik aktivis; memberikan contoh
yang “baik” dan membandingkan dengan yang “tidak baik”. Misalnya, dalam
perbincangan tanggal (satu hari setelah aksi pelayanan publik), LJK memberikan
contoh seorang ulama yang berpendirian bahwa dakwah seharusnya dilakukan
kepada “orang-orang dlolim” yang salah satunya adalah koruptor. Ulama ini
kemudian ikut dalam aksi-aksi protes yang dilakukan MCW. Dan, dalam kondisi
yang sakit pun, ia tetap mau berjalan kaki dan menolak fasilitas transportasi yang
ditawawrkan MCW. LJK terlihat sangat mengagumi orang ini. Berbeda ketia ia
bercerita mengenai alumni-alumni HMI yang memanfaatkan basis masa HMI
untuk menyukseskan karir politiknya di legislatif dan yang kemudian hari
kedapatan korupsi. Ia juga pernah mengungkapkan kekecewaannya terhadap salah
66
seorang mantan aktivis MCW yang menjadi tersangka kasus korupsi.25 “Yang
nggak habis pikir, dia itu mantan aktivis dan dulu jadi tutor pendidikan publik
anti-korupsi.” katanya
Pada kesempatan lain,26 saat seorang aktivis Indonesia Corruption Watch
(ICW) datang, relawan-relawan dan badan pekerja secara sengaja dipertemukan
dan disediakan waktu khusus untuk berbincang. Di saat itulah relawan-relawan
diberi “petuah”. Polanya mirip dengan yang dilakukan LJK, yaitu pengalaman
pribadi dan dorongan untuk bertahan tetap melakukan perjuangan masyarakat
sipil. Kata bertahan sering dimunculkan karena menurut mereka, pada
kenyataannya banyak orang yang tidak bertahan lama dalam melakukan
perjuangan masyarakat sipil.
f. FGD
Focus Group Discussion (FGD) adalah forum diskusi yang diikuti sedikit
peserta yang merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif. Forum ini
bertujuan menggali data dari peserta yang dianggap sebagai sumber data yang
spesifik dalam kasus tertentu dengan berdiskusi. Forum ini juga digunakan untuk
meminta saran dalam rancangan riset yang akan dilakukan MCW dan juga untuk
menilai hasil dari riset yang telah dilakukan. Selain itu FGD juga digunakan untuk
menghimpun pendapat ahli mengenai sebuah tema tertentu.
25 Perbincangan tanggal 19 Mei 2011 26 Bulan November, tanggal tidak tercatat
67
g. Peningkatan kapasitas
Untuk memperlengkapi relawan dengan berbagai keterampilan tertentu,
diadakanlah kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Misalnya, latihan
menganalisis APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), memahami dan
membaca KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga cara menyusun
program, dan juga bagaimana melakukan gerakan dalam mengadvokasi sebuah
kasus.
h. Diskusi
Forum-forum diskusi di MCW digunakan untuk membahas kasus korupsi
yang sedang berkembang. Diskusi mengenai perkembangan kasus korupsi yang
rutin dilakukan setiap hari sabtu pukul 13.00 WIB, sedangkan yang insidentil bisa
dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Forum diskusi juga digunakan untuk
membahas tema-tema yang disepakati menjadi pengetahuan yang perlu dimiliki
relawan (ideologi, sistem pemerintahan).
i. Publikasi
MCW sering melakukan publikasi hasil analisis mereka terhadap sebuah
kasus korupsi yang sedang berkembang melalui press release: mengirim
pernyataan pers ke media-media baik via e-mail maupun menyerahkannya
langsung kepada wartawan yang bersangkutan. Selain hasil analisis kasus, hasil
riset juga dipublikasikan melalui press conference.
j. Pelatihan
68
Dalam rangka akselerasi persiapan tiga orang untuk menjadi relawan tetap
atau badan pekerja, atas inisiatif pengurus Yayasan, diadakan rally pelatihan yang
disebut dengan in-house training.
Pelatihan ini diadakan selama tiga hari berturut-turut, pada hari Senin-
Rabu, 25-27 Oktober 2010, setiap pukul 19.00 WIB sampai selesai. Materi-materi
yang diberikan meliputi Orientasi Kelembagaan MCW, Civil Society
Organization dan Gerakan Sosial, dan Advokasi Kasus.
Diadakannya pelatihan ini dilatarbelakangi oleh keinginan
mengkonsolidasi tiga orang calon pengurus/badan pekerja sebelum ada relawan-
relawan baru yang akan menyusul masuk.
Tiga orang calon badan pekerja MCW—termasuk penulis sendiri—ini
adalah orang baru. Disebut orang baru karena memang baru terlibat secara aktif di
MCW kurang dari tiga bulan. Kami belum mempunyai perlengkapan yang cukup
untuk bisa bekerja sebagai pengurus yang terpadu di MCW. Akan menjadi
masalah jika tiga orang ini belum terkonsolidasi dan belum memiliki
perlengkapan yang cukup lalu kemudian harus memimpin relawan-relawan baru
yang menyusul masuk
Selain in-house training, pelatihan yang umum adalah pelatihan reguler
realwan. Pelatihan ini diadakan setelah sebelumnya dilakukan perekrutan terbuka.
Perekrutan dilakukan melalui penyebaran pamflet di kampus-kampus dan
sekretariat organisasi ekstra-kampus.
Ada tujuh belas orang yang mendaftar. Namun, dari tujuh belas itu, hanya
delapan orang yang serius dan bersedia mengikuti pelatihan.
69
Pelatihan diadakan dalam dua kesempatan sebagai bentuk toleransi
terhadap calon-calon relawan yang sudah terlanjur memiliki jadwal sebelum
mereka mengetahui adanya pelatihan ini. Kesempatan pertama diadakan pada
tanggal 30-31 Oktober 2010. Kesempatan kedua diadakan pada tanggal 6-7
November 2010.
Materi-materi yang diberikan meliputi (1) Orientasi Keorganisasian
Malang Corruption Watch; (2) Civil Society Organization dan Gerakan Sosial; (3)
Kerelawanan Anti-Korupsi; (4) Advokasi dan Investigasi. Sebenarnya, ini adalah
materi-materi yang sama yang diberikan pada saat in-house training. Penekanan-
penekanan yang diberikan pun sama, yaitu bahwa seorang aktivis anti-korupsi
harus menjadi seorang intelektual. Dengan kata lain, harus cerdas.27
Pelatihan yang selanjutnya diadakan pada tanggal 1-2 April 2011.
Relawan yang mengikuti pelatihan ini merupakan relawan yang hasil perekrutan
selama bulan Maret. Materi pelatihan yang diberikan sama dengan di atas.
k. Perekrutan Relawan
Selama terlibat di MCW, penulis ikut mempersiapkan dua kali perekrutan
relawan yaitu pada bulan Oktober dan bulan Maret. Dua kali perekrutan itu
dilakukan dengan cara yang hampir sama yaitu dengan menyebar pamflet di
kampus-kampus dan organisasi ekstra-kampus. Bedanya, pada perekrutan yang
27 Di balik kata cerdas ini terkandung makna mempunyai cara berpikir yang etis dan cekatan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan orang—yang menurut MCW—tertindas. Terbukti dengan kalimat yang muncul, “Mereka ini (pemerintah) kok nggak pintar-pintar ya?” (catatan lapangan, Mei 2011) pada saat seorang anggota DPRD menyatakan pemikiran yang tidak sejalan dengan MCW, yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar tidak harus gratis. Ungkapan ini juga merupakan ungkapan kekesalan.
70
pertama calon relawan tidak diwawancarai. Tapi, wawancara yang dilakukan
dalam perekrutan kedua juga tidak bertujuan untuk menyeleksi, melainkan hanya
ingin mengetahui dari ucapan mereka berapa banyak waktu yang mereka bisa
berikan bagi MCW.
Seleksi yang dilakukan terhadap relawan-relawan MCW lebih merupakan
“seleksi alam” daripada sebuah seleksi yang terstruktur. Setelah mengikuti
pelatihan-pelatihan, relawan akan langsung dilibatkan dalam kerja-kerja yang
dilakukan MCW. Di situlah akan teruji apakah mereka ‘tahan’ dengan situasi
kerja di MCW yang ternyata tidak sesuai dengan bayangan mereka. Kerja-kerja di
MCW kebanyakan menuntut kesediaan relawan untuk belajar sendiri pengetahuan
dan keterampilan yang dibutuhkan. Memang ada forum-forum peningkatan
kapasitas untuk relawan, tetapi tidak banyak.
Pekerjaan-pekerjaan di MCW kebanyakan merupakan pekerjaan yang
spontan menanggapi kasus tertentu sehingga banyak sekali rapat insidentil dan
advokasi-advokasi yang mendadak harus dilakukan. Jika seorang ingin terlibat
dalam kerja-kerja ini, ia tentu harus siap sedia tiap saat atau harus rajin datang ke
kantor untuk tahu ada pekerjaan apa di sana. Relawan yang punya kesibukan di
luar dan jarang datang ke kantor akan sangat kesulitan. Juga mereka yang tempat
tinggalnya secara geografis jauh dari MCW.
Dari pengalaman perekrutan ini, dapat juga dilihat nilai yang dipegang
teguh oleh MCW tentang bagaimana seharusnya seorang relawan itu. Relawan-
relawan yang diangkat menjadi badan pekerja adalah mereka terbukti intens
datang ke kantor MCW tanpa diminta. Di sini, penulis melihat bahwa nilai utama
71
di MCW adalah loyalitas. Beberapa relawan memiliki kapasitas intelektual yang
besar, namun karena intensitas mereka yang kurang, mereka tidak diangkat
menjadi badan pekerja. Apalagi orang-orang yang terlihat opurtunis, yang ingin
menjadikan MCW sebagai alat belaka untuk kepentingan pribadinya, atau dalam
bahasa anggota MCW “alat untuk nambahin curriculum vitae”.
Pada perekrutan pertama, dari 17 orang yang mendaftar, 8 orang ikut
pelatihan, dan sampai tulisan ini dibuat hanya ada 3 orang yang tetap aktif dan 1
orang yang kadang aktif kadang tidak. Tiga orang yang tetap aktif itu secara
geografis lokasi tinggalnya dekat denag kantor MCW. Pada perekrutan kedua,
dari 25 orang yang mendaftar, 12 orang mengikuti pelatihan, dan sampai tulisan
ini dibuat hanya tiga orang yang tetap aktif. Mereka juga adalah orang-orang yang
tempat tinggalnya dekat dengan kantor MCW.
4.1.4. Kalimetro: Lokasi Geografis Malang Corruption Watch
Kecuali aktivitas-aktivitas seperti hearing, demonstrasi, dan publikasi,
semua aktivitas MCW dilakukan di tempat yang mereka namakan Kalimetro,
terletak di bagian barat kota Malang, dahulu merupakan persawahan di Merjosari.
Bangunan kantor MCW di Kalimetro didirikan di tanah seluas 1 hektar yang
adalah tanah milik LJK. Bangunan kantor ini satu atap dengan rumah pribadi
LJK; dibatasi tembok dan pintu yang langsung menuju dapur rumah LJK.
Kantor MCW didisain sedemikian rupa untuk menjadi tempat nyaman
untuk berbincang. Dapat dilihat dengan adanya gazebo-gazebo, yang sebenarnya
juga berfungsi untuk usaha warung Kalimetro, di mana orang-orang bisa
72
menggunakan pondok itu untuk berinternet dan memesan makanan atau minuman
untuk menemani kegiatan berinternet tersebut. Kadang, gazebo-gazebo yang
letaknya di taman belakang itu juga disewa untuk acara-acara semisal acara ulang
tahun.
Ruang rapat MCW, yang terletak tepat di depan taman ber-gazebo itu
luasnya 10 x 5 meter; merupakan tempat yang selain digunakan untuk rapat, juga
digunakan untuk aktivitas-aktivitas pelatihan, FGD, pertemuan dengan jaringan,
diskusi, dan juga kadang disewakan untuk sekelompok mahasiswa yang ingin
mengadakan acara diskusi atau pelatihan di situ.
Kalimetro juga menjadi sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Malang. Hubungan MCW dengan kelompok wartawan memang sangat baik.
Mereka menjadi teman seperjuangan MCW. Wartawan mempublikasikan isu
yang sedang dibawa MCW dan juga sering membantu MCW menginformasikan
indikasi kasus korupsi di suatu lembaga.
4.2. Domain-domain Budaya yang Ditemukan
Berikut ini disajikan domain-domain budaya sekaligus taksonominya yang
telah ditemukan dari hasil pengamatan penulis selama melakukan observasi
partisipan di MCW. Domain yang telah ditemukan beserta taksonomi yang
ditampilkan merupakan hasil olahan atau analisis dari catatan lapangan. Dengan
kata lain, bagian merupakan sajian analisis domain dan taksonomi.
Sesuai dengan masalah yang dibahas, domain budaya yang dihadirkan di
bawah ini dibatasi menjadi (1) Domain yang berhubungan perilaku politik; (2)
73
Domain yang berhubungan budaya/pengetahuan politik; dan (3) Domain yang
berhubungan dengan bagaimana budaya/pengetahuan politik itu diwariskan.
4.2.1 Domain budaya yang berhubungan dengan perilaku politik
Dalam beberapa pertemuan, LJK sering mengkategorikan bagaimana
berpolitik. Ia membedakan antara politik nilai dan politik kekuasaan. Politik
kekuasaan sering diidentikkan dengan perilaku politik anggota legislatif atau siapa
pun yang menggunakan kancah politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan.
Sedangkan politik nilai digambarkan sebagai politik yang beretika; politik yang
dilakukan sebagai alat untuk berpihak pada kemanusiaan. LJK pernah
mengatakan,
“Politik itu hadir karena memberi kebajikan. Kalau masuk politik ya harus hadirkan kebajikan. Dalam konteks ini ide hadir...kekuasaan itu efektif ketika kita ingin membangun kebajikan. Kekuasaan itu instrumen untuk hadirkan kebajikan. Sekarang kan dibalik.”28
Tabel 4. Macam Politik Menurut MCW29 Kinds of Politics
1. Politik Nilai 2. Politik Kekuasaan
Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Domain selanjutnya adalah kinds of activites, atau macam-macam
aktivitas, yang tentunya yang berhubungan dengan politik. Di dalam macam
28 Diskusi tanggal 13 Juni 2011 29 Sumber ide dari “Macam Politik Menurut MCW” adalah LJK sehingga “Macam Politik Menurut MCW” bisa dikatakan sama dengan “Macam Politik Menurut LJK”. Ini dikarenakan LJK adalah aktor dengan PAu; dan bahwa aktor dengan PAu inilah yang menjadi sumber ide-ide yang ada di MCW. Dalam pembahasan selanjutnya, dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan MCW berikutnya dasar perilakunya memang adalah ide LJK.
74
aktivitas ini, juga dapat dilihat bagaimana anggota MCW berperilaku terhadap
pemerintah.
Tabel 5. Macam Aktivitas Politik MCW Kind of Activities
1. Rapat Konsultasi dan Pengorganisasian 2. Multistakeholder meeting 3. Diskusi Publik 4. Pertemuan Konsolidasi 5. Aksi Demonstrasi 6. Mendatangi DPRD dan memaksa bertemu 7. Berargumen dengan pemerintah/DPRD 8. Melayangkan surat tuntutan 9. Melayangkan surat pernyataan keberatan 10. Memberikan pernyataan pers untuk menekan pemerintah
Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Aktivitas yang pertama adalah konsultasi dan pengorganisasian
dampingan. Beberapa kali penulis pernah mengikuti rapat konsultasi dampingan
di kantor MCW. Saat itu, MCW sedang mengadvokasi kasus modernisasi
pedagang pasar Dinoyo dan Blimbing.
Pada tanggal 4 Oktober 2010, sekelompok pedagang pasar Blimbing
datang ke kantor MCW. Ada lima orang pedagang yang datang. Mereka mengaku
direkomendasikan oleh seorang teman yang mereka percayai untuk datang ke
MCW meminta bantuan. Hasil pembicaraan saat itu adalah Pedagang Blimbing
perlu menyediakan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pemerintah telah
memutuskan bahwa tanah yang mereka tempati sekarang diperuntukkan bagi
pasar. Mereka juga diharapkan bisa mengumpulkan data seluruh pedagang pasar.
75
Pada tanggal 6 Oktober 2010, diadakan pertemuan dengan pedagang Pasar
Dinoyo. Pertemuan ini dilakukan pada malam hari Pk. 20.20. Hadir hampir
seluruh pengurus Paguyuban Pedagang Dinoyo. Dalam pertemuan ini, dibicarakan
bersama langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengadvokasi kebijakan
pemerintah. LJK bertindak sebagai fasilitator yang memandu pedagang untuk
menyusun strategi gerakan (melihat siapa kawan dan lawan, dsb.). Dalam rapat ini
diputuskan juga bahwa akan diadakan pertemuan dengan akademisi untuk
menggalang dukungan bagi Pedagang Pasar Dinoyo.
Lalu, pada tanggal 23 Oktober 2010 diadakan pertemuan penggalangan
dana dari akademisi untuk pedagang Dinoyo. Pertemuan ini diadakan di
Universitas Muhammadiyah Malang, di mana akademisi diminta untuk
memberikan kajian mengenai masalah relokasi Pedagang Pasar Dinoyo. Dalam
pertemuan ini terjadi diskusi dan akhirnya menghasilkan keputusan bahwa
akademisi akan ditugasi melakukan kajian terhadap Pasar Dinoyo untuk
memberikan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menilai kebijakan
pemerintah mendirikan mall dan apartemen di lokasi Pasar Dinoyo. Kajian yang
dilakukan disepakati menjadi dua, yaitu bersifat hukum dan non-hukum. Kajian
non-hukum dilakukan oleh dosen-dosen ilmu sosial sedangkan kajian hukum
dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya cabang Malang dan dua orang
advokat jaringan MCW.
Selain aktivitas pengorganisasian di atas, beberapa alat juga digunakan
oleh MCW untuk mengadvokasi kebijakan. Pada tanggal 23 Oktober-14
November 2010, MCW bersama Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Cabang
76
Malang membuat opini hukum; sebuah tulisan argumen hukum yang menilai
sebuah kebijakan. MCW bertugas menyediakan segala dokumen yang perlu untuk
membuat argumen hukum mengkonfrontasi argumen pemerintah. Argumen
hukum ini dibuat oleh dua orang advokat yang secara sukarela menyediakan
tenaganya (tanpa dibayar). Relawan dan badan pekerja terlibat dalam
menyediakan data-data yang perlu dan memberikannya pada dua orang advokat
itu. Setelah argumen hukum, dibuatlah kajian akdemis. Pada tanggal 15
November 2010 diadakan expert meeting atau pertemuan ahli (akademisi) untuk
membuat kajian mengenai modernisasi pasar Dinoyo. Pertemuan ini dihadiri oleh
akademisi-akademisi yang bersedia membantu membuat kajian. Setelah ada
paparan dari masing-masing ahli, rapat berakhir dengan pembagian tugas di antara
akademisi-akademisi yang hadir untuk membuat kajian-kajian. Lalu, pada tanggal
04-24 Oktober 2010 MCW bersama seorang akademisi Universitas
Muhammadiyah Malang melakukan survey “Studi Pengetahuan dan Sikap
masyarakat Sekitar Terhadap Modernisasi pasar Dinoyo”. Hasil survey ini
kemudian dipublikasikan di rumah makan “Ringin Asri”. Yang diundang adalah
wartawan, enumerator, dan jaringan MCW. Presentasi hasil survey dilakukan oleh
Rahmat K.D.S, ketua tim peneliti (akademisi dari UMM). Akhir dari publikasi ini
disepakati untuk dilakukan langkah konkret menyampaikan hasil penelitian ini
kepada pemerintah.
Aksi demonstrasi juga pernah dilakukan. Pada tanggal 25 November 2010,
sekitar 600 orang melakukan demosntrasi di balai kota. Elemen-elemen massa
yang ikut di dalamnya antara lain Pedagang Pasar Dinoyo dan Blimbing,
77
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Cabang Malang, MCW, dan Perjuangan
Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Islam Malang. Aksi dimulai
sekitar pukul 08.00 WIB dan diakhiri pukul 14.00 setelah berhasil menemui
Sekretaris Daerah. Dalam aksi tersebut, LJK dan pedagang memang keras ingin
bertemu dengan Walikota, walaupun akhirnya hanya bertemu sekretaris daerah.
Dan, kalimat-kalimat yang sifatnya menekan juga dilontarkan dalam aksi tersebut.
Aksi ini dikoordinasi pedagang Dinoyo satu hari sebelumnya dan mengundang
LJK untuk dimintai saran tentang bagaimana sebaiknya aksi ini dilakukan.
Malang Corruption Watch juga pernah mengadakan multistakeholder
meeting di rumah makan Ringin Asri yang diadakan pada tanggal 17 Februari
2011. Multistakeholder meeting adalah pertemuan yang mengundang baik
pemerintah, masyarakat awam, akademisi, maupun NGO untuk duduk bersama
membicarakan suatu tema. Saat itu, tema yang diangkat adalah pelayanan publik.
Masyarakat awam diminta menyampaikan usulan dan keluhannya, kemudian
pemerintah atau dinas yang terkait bisa menjawab atau menjelaskan usaha
pelayanan mereka selama ini. Pada akhir pertemuan, tercipta komitmen bersama
untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik di Malang. Komitmen itu
masih abstrak dan kesepakatan untuk bertemu lagi membicarakan langkah-
langkah yang teknis tidak pernah terealisasikan hingga skripsi ini ditulis.
Salah satu kegiatan yang kemudian juga bisa dilihat sebagai salah satu
contoh perilaku politik MCW adalah diskusi publik. Salah satunya adalah yang
pernah diadakan di ruang sidang DPRD Kota Malang pada tanggal 28 Maret
78
2011.30 Pertemuan ini diawali dengan informasi kesediaan ketua DPRD Kota
Malang untuk meyediakan fasilitas berupa tempat dan makanan untuk berdiskusi
dengan dewan mengenai modernisasi Pasar Dinoyo dan Blimbing. Kesempatan
ini digunakan MCW dan kelompok pedagang untuk berdialog secara persuasif
untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam pertemuan yang dikemas secara formal
ini, MCW dan pedagang mengundang akademisi yang diminta memberikan
pendapatnya tentang modernisasi pasar tradisional. Dewan dan pemerintah kota
juga diberi kesempatan untuk bersuara.
Aktivitas berikutnya adalah konsolidasi. Usaha konsolidasi yang pernah
dilakukan MCW selama penulis melakukan observasi-partisipan di sana adalah
pembentukan konsorsium masyarakat peduli publik Malang. Usaha ini dilakukan
pada tanggal 20 Februari 2011. Berdasarkan apa yang didengar dalam awal
pembicaraan pertemuan itu, pertemuan ini dilakukan karena beberapa aktivis
‘kangen’ (rindu) untuk kembali bertemu dan membangun gerakan lagi.
Pertemuan itu didasari kenyataan bahwa gerakan masyarakat sipil di kota
Malang kurang terkonsolidasi satu sampai dua tahun belakangan ini. Gerakan
oposisi ini terpecah karena pemilihan kepala daerah, seperti yang diakatakan Mas
Pupung31, “Awal cerai berai kan Pilkada. Dulu padahal bisa jalan bareng,
sekalipun ndak ada uang. Pos pengaduan bisa jalan walau tanpa uang.” Pada
malam itu, memang pembicaraan diawali dengan cerita tentang orang-orang yang
memilih ‘jalan lain’, atau tidak lagi dalam pilihan gerakan oposisi. Ada yang
30 Walaupun diskusi publik ini diorganisir bersama oleh MCW dan Pedagang Dinoyo, Pedagang mengambil peran lebih banyak dalam mempersiapkan acara ini. Acara ini juga diatasnamakan persatuan pedagang Dinoyo, bukan MCW. 31 Nama aslinya adalah Purnawan D. Negara. Ia adalah aktivis Wahana Lingkungan Hidup Malang. Dosen Hukum di Universitas Widyagama Malang.
79
masuk dalam struktur pemerintahan, ada pula yang menjadi konsultan hukum
perusahaan yang bermasalah dengan pengrusakan lingkungan. Semua ini terkesan
menjadi ‘contoh yang tidak baik’ dalam gerakan mereka.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan bagaimana
konsorsium tersebut akan membangun gerakannya. Mereka memulai dengan
mengevaluasi langkah yang selama ini mereka ambil dalam melakukan gerakan.
Bintoro, seorang aktivis yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan MCW tiga
tahun lalu berkata,
“Kita lelah karena memang masyarakat terus datang pada kita, karena mereka percayanya sama kita. Kita pernah kampanye soalnya. Kita perlu bikin koalisi baru; kasus terus bergulir soalnya, supaya masalah-masalah bisa diselesaikan. Kita bisa bergerak”32
Ia juga menambahkan bahwa selama ini cara kerja aktivis seperti pemadam
kebakaran, menyelesaikan kasus demi kasus.
Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang yang peduli terhadap politik Kota
Malang dan selalu berkeinginan untuk membangun gerakan perlawanan terhadap
apa yang mereka anggap sebagai masalah. Seperti kata Bintoro, “Koyok awake
dewe sing nduwe-nduwene Malang ae. Tapi yo ancene kene wong Malang.”33
Perilaku yang paling sering penulis amati dalam aktivitas-aktivitas MCW
adalah menekan pemerintah mengingat mereka adalah organisasi watchdog yang
tugasnya tidak lain adalah mengontrol kinerja pemerintah bahkan menekan jika
kinerjanya dianggap tidak baik. Penekanan ini dilakukan melalui media. MCW
memberikan pernyataan pers yang menilai pemerintah ini dan itu. Misalnya,
32 Catatan lapangan, 20 Februari 2011 33 Bahasa Jawa. Artinya, “Seolah-olah kita inilah pemilik kota Malang. Tapi memang kita ini orang Malang.”
80
ketika itu Walikota Malang mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan
pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 % untuk zakat, infaq, dan sadakah. MCW lalu
melakukan rapat insidentil, menganalisis segi hukum dan sosiologis dari
kebijakan itu34. Setelah itu, MCW melakukan rilis pers yang berisi penolakan
terhadap kebijakan itu sehari setelah rapat. Yang terasa saat melakukan advokasi
kasus semacam ini adalah berkejarnya anggota MCW dengan waktu. Mereka
selalu berusaha untuk mengeluarkan pernyataan pers di momen yang tepat.
Kejadian yang lain adalah pada masa penerimaan siswa baru tahun ajaran
2011/2012 Malang, bulan Juni-Juli 2011. MCW bersama Forum Masyarakat
Peduli Pendidikan (FMPP)35 menerima pengaduan dari masyarakat. Beberapa
wali murid mengadu karena dikenakan biaya pendidikan yang tinggi. Juga wali
murid SD dan SMP Negeri yang ditarik pungutan. Padahal, menurut aturan yang
berlaku program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) harus
bebas biaya. Setelah rapat dengan FMPP, MCW melakukan rapat penyusunan
analisis kritis terhadap fenomena pendidikan kota Malang, tanggal 26 Juni 2011.
Esok harinya, tanggal 27 Juni 2011, MCW mendatangi kantor DPRD Malang
untuk menyerahkan surat tuntutan pembebasan biaya pendidikan program wajib
belajar. Saat tiba di kantor DPRD, LJK langsung menelepon beberapa wartawan
setelah menemukan tidak semua berada di kantor DPRD. Setelah wartawan
datang, kami duduk dan menunjukkan surat yang kami bawa. Beberapa wartawan
menanyai. Sesaat kemudian, asisten komisi D keluar dan memberitahukan bahwa
34 Dilakukan pada awal bulan Mei 2011 35 Forum Masyarakat Peduli Pendidikan adalah kelompok kerja yang dibentuk MCW di bawah Divisi Pelayanan Publik, beranggotakan orang-orang usia 40-60an yang bertugas mengadvokasi kasus-kasus diskriminasi dalam pendidikan.
81
komisi D sedang rapat. Saat itu LJK berkata, “Kalau begitu kita tinggal aja
suratnya di sini, bilang bahwa Komisi D tidak mau menerima kita.”
“Yo ojo ngono to yo...”36 kata asisten. LJK hanya menanggapi dengan
muka masam. Si asisten masuk kembali dan tidak lama Sutiaji, anggota komisi D
DPRD Kota Malang yang sering berhubungan dengan MCW keluar. “Ayo mas,
masuk ae,” kata Sutiaji, dan menambahkan dengan nada pelan, “Sabar a mas,”37
Gambaran ini adalah contoh bagaimana MCW memiliki perilaku yang cenderung
represif terhadap negara.38 Selain dengan cara-cara seperti digambarkan di atas,
MCW juga menggunakan media untuk “takut-takutin mereka (pemerintah)” 39
Selain surat tuntutan, MCW juga pernah melayangkan surat pengajuan
keberatan. Surat ini dilayangkan karena permohonan informasi mereka atas
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD kota Malang 2011 tidak
dikabulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Pelayangan
surat itu pun di-blow up di media. Sebelum berangkat ke Balai Kota, MCW
datang ke warung Rindam, yang merupakan markas wartawan. Dilakukanlah
koordinasi di situ dan kemudian wartawan meliput aktivitas pelayangan surat itu.
Sesudahnya, MCW memberi pernyataan di media, menuduh pemerintah kota
tidak transparan.
Terlihat bahwa MCW memanfaatkan semua elemen yang bisa
mendukung apa yang sedang mereka perjuangkan. Alat-alat opini hukum, kajian
akademis, dan riset atau survei juga digunakan sebagai alat untuk melegitimasi
36 Bahasa Jawa, artinya “Ya jangan begitu,” 37 Catatan lapangan, 27 Juni 2011 38 Istilah negara sering diidentikkan dengan legislatif dan eksekutif. 39 LJK, dalam catatan lapangan, 26 Juni 2011.
82
langkah yang mereka lakukan untuk mengubah kebijakan. Cara- cara yang
digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pun bervariasi, mulai dari yang
konfrontatif (pressure di media, aksi demonstrasi, nglurug) hingga yang
kooperatif (diskusi publik, hearing).
4.2.2. Domain budaya yang berhubungan dengan budaya politik
Seperti yang sudah dibatasi dalam Bab II, yang dimaksud budaya adalah
seperangkat pengetahuan yang mendasari perilaku tertentu. Maka, dalam bagian
ini akan dipaparkan pengetahuan-pengetahuan yang mendasari aktivitas dan
perilaku politik MCW yang sebelumnya telah dipaparkan di atas. Domain itu
terdiri dari kinds of goals (macam-macam tujuan), reasons for goals (alasan-
alasan dari tujuan tersebut), dan reasons for activities (alasan-alasan dari aktivitas
yang dilakukan, terutama aktivitas politik). Dilihat bahwa alasan dari segala
sesuatu yang dilakukan dan dituju MCW bisa menjadi cermin dari pengetahuan
apa yang mendasari gerakan MCW. Dalam tabel yang berisi domain alasan-alasan
(reasons for goals dan reasons for activities), penulis menomori alasan-alasan
tersebut sesuai dengan tabel kinds of goals dan kinds of activities. Misalnya,
dalam tabel reasons for goals, yang dinomori (a) adalah alasan dari goals nomor
(a). Dalam domain-domain yang berkaitan dengan alasan-alasan, pembaca akan
menemukan kata-kata taken for granted. Sesuatu dikatakan sebagai taken for
granted ketika ia dijadikan dasar dari suatu perilaku tanpa mempertanyakan
alasan dari hal itu.
83
Tabel 6. Taksonomi budaya yang berhubungan dengan budaya politik Kinds of Goals
1. Eksternal a. Membangun peradaban b. Menciptakan masyarakat madani c. Menciptakan tatanan masyarakat yang adil d. Mengubah kebijakan yang merugikan e. Menciptakan Pelayanan Publik yang baik f. Memberi harapan pada jaringan g. Membangun blok politik
2. Internal a. Mendapatkan dana b. Memberi panggung dan memunculkan aktor-aktor baru c. Mengkonsolidasi relawan d. Mempertahankan relawan e. Mendapatkan relawan f. Meningkatkan kapasitas relawan g. Menjadikan MCW lembaga yang kredibel h. Menjadikan MCW lembaga yang dipercaya masyarakat i. Membangun tradisi intelektual
3. Pribadi a. Dapat pahala b. Belajar c. Masuk surga d. Berbuat baik
Reasons of Goals 1. Eksternal
a. taken for granted b. taken for granted; referensi dari sejarah agama Islam atau “apa
yang dahulu dilakukan Nabi” c. taken for granted d. karena yang lemah harus diperhatikan e. taken for granted f. karena mereka butuh harapan, supaya mereka tetap hidup, punya
semangat g. supaya masyarakat bisa punya kekuatan vis a vis negara
2. Internal a. Dana, walaupun bukan satu-satunya, adalah sesuatu yang
menghidupkan teman-teman gerakkan b. ‘Karena kita bukan partai politik, yang cuma ada satu matahari
(aktor yang menonjol). Kita harus banyak mataharinya’ c. Karena pekerjaan yang tidak terkonsolidasi akan menjadi
pekerjaan yang buruk d. Karena ini bukan lembaga politik yang suka membuang orang e. Karena mahasiswa adalah mata air gerakkan; bahwa MCW adalah
lembaga kaderisasi
84
f. taken for granted g. taken for granted h. taken for granted i. Karena kita ini intelektual, bukan preman, harus memakai cara-
cara yang beradab 3. Pribadi
a. taken for granted b. taken for granted c. taken for granted
Reasons of Activities
1. Membangun gerakan tidak boleh sembarangan 2. Pemerintah, dengan tujuan-tujuan tertentu dapat duduk satu meja dengan
kita 3. Publik harus tahu isu yang sedang berkembang sehingga bisa mendukung
gerakan 4. Melawan pemerintah harus dengan kekuatan yang terorganisir 5. Pemerintah harus ditekan 6. DPRD adalah wakil rakyat, wajib menemui rakyat ketika didatangi 7. ‘Kita ini lebih pintar dari mereka (pemerintah)’ 8. Fenomena ini melanggar hukum 9. Tuntutan masyarakat tidak dipenuhi 10. MCW hadir untuk mengontrol pemerintah
Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Setidaknya ada tiga sifat tujuan-tujuan yang ada di MCW.40 Pertama,
eksternal. Tujuan eksternal berkaitan dengan misi MCW; apa saja yang ingin
dicapai di kota Malang dengan hadirnya MCW. Kedua, internal. Tujuan internal
adalah hal-hal apa yang ingin dicapai di dalam organisasi MCW itu sendiri.
Ketiga, pribadi. Tujuan-tujuan pribadi ini adalah tujuan-tujuan yang penulis
temukan dalam diri relawan-relawan MCW yang berkaitan dengan hidup mereka
pribadi.
40 Pembagian tujuan ke dalam tiga sifat ini merupakan kesimpulan penulis sendiri berdasarkan apa yang telah ditemui di lapangan, bukan dari mulut informan sendiri. Mereka mengungkapkannya dengan istilah yang berbeda-beda. Lihat pembahasan halaman 109-110
85
Yang paling penting dilihat adalah tujuan eksternal karena hal ini
berkaitan dengan misi MCW—segala sesuatu yang mendasari perilaku politik
MCW, walaupun ini tidak mengesampingkan jenis tujuan yang kedua dan ketiga.
Jenis tujuan yang kedua dan ketiga akan melengkapi jenis tujuan yang pertama
supaya ada gambaran yang lebih luas mengenai pengetahuan yang mendasari
perilaku politik mereka—tidak hanya tujuan bersama, tetapi juga tujuan pribadi
yang merupakan hal yang lebih mendasar lagi dari perilaku mereka.
Apa yang menjadi isu utama LJK dan kelihatannya menjadi penggerak
utamanya adalah pemberadaban, seperti yang pernah dikatakan saat berbincang
setelah rapat Badan Pekerja, hari Jumat, 29 April 2011, “Sebenarnya semua itu
(gerakan NGO) didasari pada kenginan kita untuk membentuk keadaban atau
civilitas...Kalau kita jadi aktivis sosial, tapi kita tidak beradab kan susah.”
LJK berpendapat bahwa tujuan utama dari gerakan sosial yang dilakukan
MCW adalah membangun masyarakat yang beradab. Ia selalu terkesan dengan
cara-cara yang beradab. Dalam waktu-waktu perbincangan dengannya, “beradab”
terasa sebagai kata yang sakral, yang mulia, yang merupakan tujuan tertinggi yang
sedang dicapai perjuangan-perjuangannya. Beberapa kali dalam perbincangan ia
juga mengambil referensi dari ide Nurcholis Madjid tentang masyarakat madani.
Ide tentang masyarakat madani ini menjadi salah satu pengejewantahan dari
mimpi besar tentang peradaban. Lalu, masyarakat yang adil menjadi tujuan yang
lebih nyata lagi. Dan, LJK sering mengacu pada Karl Marx ketika berbicara
mengenai keadilan.
86
Mengubah kebijakan yang merugikan adalah bentuk yang lebih nyata lagi
dari ide menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Kebijakan yang merugikan
bisa dihentikan jika ada pelayanan publik yang baik. Maka, pelayanan publik
yang baik juga menjadi tujuan yang ingin dicapai MCW dan inilah yang sesuai
dengan spesifikasi gerakan MCW, yaitu gerakan anti-korupsi. Tetapi, spesifiknya
perjuangan MCW dalam ranah gerakan anti-korupsi tidak menjadikan MCW
hanya mengerjakan hal itu. Dalam prakteknya, MCW bahkan juga menjalankan
fungsi advokasi, misalnya dalam kasus modernisasi Pasar Dinoyo dan Blimbing
yang sudah dijelaskan di atas dan juga mengadvokasi kasus penerimaan siswa
baru di mana banyak orang tua murid yang mengalami kesulitan karena harus
membayar uang pendaftaran yang mahal. Terlihat bahwa nilai yang dipegang
MCW adalah kepedulian. Yang menjadi nilai utama adalah “peduli saat rakyat
berteriak,” seperti yang pernah dialami penulis saat menyusun surat analisis kritis
untuk menanggapi kasus-kasus pungutan dalam penerimaan siswa baru Kota
Malang. Saat itu kami berkumpul di kantor MCW pada tanggal 26 Juni 2011
mulai pukul 19.00 untuk menyusun surat analisis kritis mengenai penerimaan
siswa baru Kota Malang. Memulai pertemuan, LJK berkata,
“Sebelum masuk substansi, aku mau bilang gini dulu. Saya baca koran, ternyata banyak sekali berita tentang PSB. Dan, kita nggak melakukan apa-apa. Cuma melakukan tindakan heroik. Advokasi ke sekolah ini sekolah itu. Itu tindakan memadamkan api. Kita harusnya mempengaruhi kebijakan. Ini rakyat sudah berteriak, kalau kita nggak melakukan apa-apa, menurut saya itu berdosa.”41
Berkaitan dengan membangun gerakan pemberadaban masyarakat, MCW
tentu harus memelihara organisasi dan perkumpulan yang berjejaring dengannya.
41 Catatan lapangan, Minggu, 26 Juni 2011.
87
LJK menyadari hal ini. Dan merasa bahwa MCW adalah katalisator bagi gerakan
itu di Kota Malang. Maka, MCW harus terus memberi harapan kepada jaringan
supaya mereka terus memiliki idealisme dan bergerak untuk membangun
masyarakat yang beradab.
Salah satu tujuan internal MCW adalah mendapatkan dana. Mereka
mengakui bahwa uang adalah hal yang penting, meskipun bukan yang utama.
Disadari bahwa gerakan mereka membutuhkan fasilitas dan penyediaan fasilitas
membutuhkan uang. Berbagai aktivitas pun dilakukan untuk menggalang dana,
seperti mendirikan usaha penerbitan dan warung sehingga kebutuhan operasional
sehari-hari bisa terpenuhi. Ketika pengurus baik yayasan maupun badan pekerja
MCW menjadi fasilitator atau diundang sebagai pembicara dan mendapat uang
transpor atau apresiasi, uang itu langsung dimasukkan dalam kas MCW sebagai
tabungan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan.
Yang diharamkan untuk diterima adalah uang dari obyek pantau, yaitu
pemerintah, legislatif, maupun perusahaan yang dianggap bermasalah.
Independensi memang adalah nilai yang paling dijaga di MCW. Mereka menjaga
supaya tidak bisa dipengaruhi oleh obyek pantau.
“Dulu kami pernah ditawari uang segebok oleh Kepala Dinas ‘X’. Segebok, Di. Kalau mau ya kita ambil. Tapi masa harga diri kita serendah itu? Kacau memang orang itu. Kok ya nggak malu itu lo”42
Tujuan-tujuan kecil lain yang dituju MCW adalah memberi panggung
kepada aktor-aktor baru, misalnya, memunculkan ke khalayak banyak seorang
ahli kebijakan publik, atau ahli hukum, atau yang lain dengan cara menjadikan
42 LJK, pada saat perbincangan informal pada tanggal 3 Februari 2011.
88
mereka pemateri atau pembicara dalam diskusi-diskusi publik yang diadakan
MCW. “Karena kita ini bukan partai politik, yang cuma punya satu matahari. Di
sini mataharinya harus banyak.” Kata LJK dalam perbincangan informal pada
bulan November 2010.
Didit, koordinator MCW, pernah berkata, “Mahasiswa adalah mata air
gerakan.”43 Karena itu tujuan-tujuan kegiatan MCW adalah juga mendapatkan,
mengkonsolidasi, mempertahankan, dan meningkatkan kapasitas relawan yang
seratus persen adalah mahasiswa. Diskusi-diskusi, perbincangan informal, tugas-
tugas pendampingan, bahkan kerja bakti adalah sarana-sarana untuk
mempetahankan dan mempererat hubungan antar-relawan.
Rapat-rapat evaluasi dan perbincangan insidentil yang sifatnya evaulatif
digunakan untuk memenuhi tujuan berikutnya, yaitu menjadikan MCW lembaga
yang kredibel dan dipercaya masyarakat. “Aku yang gini-gini merhatiin betul.
Jangan sampai kita kelihatan plonga-plongo di depan mereka.”44 Ketatnya aturan
MCW untuk tidak menerima dana dari obyek pantau juga menjadi cara untuk
membuat lembaga ini kredibel.
Tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah membangun tradisi
intelektual di MCW. Ini lebih merupakan konsekuensi langsung karena LJK
sendiri menahbiskan diri dan kelompoknya sebagai kaum intelektual yang sedang
berjuang untuk membangun peradaban; membangun masyarakat yang adil dan
bebas penindasan.
43 Perbincangan informal Desember 2010 44 LJK, saat mendampingi relawan mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kota Malang pada tanggal 4 Juli 2011. Ia meminta relawan untuk mengatur bagaimana mereka akan menampilkan diri di depan dewan dan walikota.
89
Menarik juga untuk ditinjau apa tujuan-tujuan pribadi anggota-anggota
MCW. Penulis melihat ada hal yang taken for granted dalam diri masing-masing
mereka, yaitu mendapat pahala dan masuk surga; tidak lain karena anggota MCW
adalah orang-orang yang religius sehingga apa yang mereka lakukan juga salah
satunya didorong oleh motif ketaatan beragama. Seperti yang pernah dikatakan
Didit, “Dik, tadi aku lihat orang bawa-bawa kambing. Aku nganter undangan.
Wadoh, berat ini. Tapi jalan ke surga tidak hanya melalui ibadah kan?”45 dan LJK,
“Kalau saya kaya, ya gampang. Tinggal bangun masjid yang banyak saja. Dapat
pahala dan masuk surga. Tapi saya nggak kaya. Jadi, kesempatan saya untuk
berbuat baik adalah melalui kerja-kerja seperti ini”46
Selain motivasi religius yang juga taken for granted adalah motivasi untuk
belajar. Semua menyetujui bahwa yang hadir di MCW berkeinginan untuk belajar
dan mengembangkan diri. Pada perbincangan tanggal 12 Oktober 2010, LJK
mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh relawan MCW. Yang
pertama adalah menjaga integritas. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dan
perawatan idealisme. Yang kedua adalah kapasitas. Hal ini berkaitan dengan
kemampuan-kemampuan praktis dan intelektual yang dibutuhkan seseorang untuk
bekerja di sebuah lembaga yang mendampingi masyarakat.
Beberapa pengetahuan yang mendasari aktivitas-aktivitas MCW juga
dapat ditemukan. Mengenai dilakukannya rapat konsultasi dan pengorganisasian,
sering muncul kalimat bahwa segala sesuatu harus diorganisasikan dengan baik.
Pekerjaan NGO harus profesional, bahkan lebih baik daripada pemerintah. Lalu,
45 Pada saat Idul Adha, tanggal 17 November 2010 46 Tanggal tidak tercatat
90
mengenai aktivitas multistakeholder meeting, ditemukan pendapat yang sering
terlontar bahwa tidak selalu aktivitas MCW bersifat menyerang pemerintah, tapi
juga bisa duduk bersama dan bernegosiasi.47 Mengenai aktivitas diskusi publik
dan konsolidasi, pengetahuan yang mendasarinya adalah kesadaran bahwa perlu
dibangun sebuah kekuatan yang besar dari masyarakat untuk melawan
pemerintah. Ini penulis amati dari diskusi-diskusi yang dilakukan dalam
pertemuan-pertemuan konsolidasi. Pentingnya konsolidasi juga terlihat dari
kalimat yang diungkapkan LJK, “Gimana mau lawan Peni, konsolidasi aja masih
sulit.”48
Selain aktivitas, beberapa pengetahuan yang mendasari perilaku anggota
MCW dalam aktivitas yang mereka lakukan juga ditemukan. Mengenai
memberikan pernyataan pers untuk menekan pemerintah, MCW memang
mengambil posisi sebagai pengontrol atau watchdog (bahasa penulis) terlihat dari
sinisnya mereka ketika melihat seorang teman yang akhirnya bergabung dengan
pemerintah. Memang, dalam beberapa kesempatan perbincangan LJK mengatakan
bahwa itu adalah pilihan dan sah-sah saja. Namun, penulis mengamati gesture
yang sinis dan kesempatan yang lain. Mengenai “pemaksaan” untuk menemui
DPRD yang sudah penulis deskripsikan di atas, pengetahuan yang mendasarinya
adalah bahwa DPRD adalah wakil rakyat, seharusnya menerima siapa pun yang
datang. Kalimat LJK yang mengancam akan memberitakan ke media bahwa
DPRD menolak menerima kedatangan MCW dan respon panik dari anggota
47 Pendapat-pendapat ini penulis amati ketika persiapan dan kegiatan beres-beres ruangan setelah acara multistakeholder meeting dilaksanakan. Penulis melihatnya dari kalimat-kalimat spontan yang muncul dari badan pekerja MCW dan LJK. 48 Diungkapkan pada tanggal 23 Juli 2011, saat salah satu organisasi buruh di Malang mengadakan acara konsolidasi di MCW, tapi tidak ada yang datang.
91
DPRD itu menyimpulkan bahwa ada satu aturan yang dipegang bersama bahwa
DRPD harus menerima rakyat atau setidaknya harus terlihat menerima rakyat.
Seringnya muncul kalimat, “Kita ini lebih pintar dari mereka
(pemerintah/DPRD),” menunjukkan keyakinan bahwa anggota MCW lebih pintar
dari pemerintah dan ini yang membuat mereka yakin berargumen dengan
pemerintah. Selain itu, ada satu filosofi bahwa pemerintah tidak bisa berlaku
semaunya terhadapan masyarakat. Mereka tidak berada di atas masyarakat. Ini
penulis amati ketika DPRD mengundang MCW untuk bertemu, LJK mengatakan
bahwa mereka harus mengirimkan surat resmi, “Enak aja mereka. Kalo ngundang
lembaga ya harus prosedural. Ini lembaga coy!”49 Surat-surat tuntutan dan
keberatan yang terus-menerus dikirim MCW menunjukkan pengetahuan yang
mendasarinya, yaitu bahwa masyarakat harus terus mengontrol pemerintah.
4.2.3. Domain budaya yang berhubungan dengan pewarisan budaya politik
Dalam domain budaya yang berhubungan dengan pewarisan budaya
politik, penulis menampilkan satu domain saja, yaitu “Cara Pengimposisian
Budaya”. Seperti yang sudah dibahas dalam Bab II, pengimposisian budaya
termasuk dalam pedagogic work, baik yang eksplisit (melalui sistem yang dibuat
secara sengaja) maupun implisit (dilakukan secara spontan melalui praktik-praktik
dan pelibatan-pelibatan tertentu dalam praktik-praktik). Selain itu, pengimposisian
budaya atau yang lebih spesifik pewarisan modal budaya (habitus) juga
melibatkan pengalaman sejarah mengingat apa yang dikatakan Bourdieu bahwa
49 Perbincangan tanggal 1 Juli 2011
92
habitus tidak lain merupakan, “the active presence of the whole past of which it is
the product” atau kehadiran yang aktif dari keseluruhan masa lalu (Bourdieu,
1990:53). Lebih lanjut menurut Bourdieu, masa lalu atau sejarah itu berfungsi
sebagai accumulated capital. Berangkat dari pemahaman di atas, penulis
menemukan beberapa cara pengimposisian budaya. Cara-cara itu sebagai berikut:
Tabel 7. Pengimposisian budaya politik di MCW Ways of Mengimposisikan Budaya Politik 1. Pemagaran-pemagaran tertentu terhadap perilaku:
a. Melalui etika kerja yang tertulis secara spesifik b. Kalimat-kalimat spontan dalam kegiatan-kegiatan
2. Pengharusan-pengharusan tertentu 3. Pengkondisian-pengkondisian tertentu
a. Diberi tanggung jawab tertentu dalam aktivitas politik b. Dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas politik
4. Pemberian nasihat-nasihat 5. Pengimposisian yang monopolistis mengenai habitus/etika tertentu dalam
diskusi dan ceramah 6. Training Relawan Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Cara yang pertama dalam mengimposisikan budaya atau habitus politik
adalah dengan melakukan pemagaran atau pelarangan-pelarangan tertentu
terhadap perilaku relawan atau anggota badan pekerja. Pelarangan-pelarangan itu
dilakukan secara eksplisit melalui etika kerja tertulis yang disepakati bersama dan
kalimat-kalimat larangan yang langsung dalam kegiatan-kegiatan yang sedang
dilakukan. Larangan-larangan itu adalah (a) menerima uang dari obyek pantau; (b)
melakukan pemantauan sendiri; (c) memonopoli kemunculan di media; (d) “mau
disuruh-suruh pemerintah”; (e) bersikap takut terhadap aparat pemerintahan
Dua larangan yang pertama adalah larangan yang secara eksplisit tertulis
dalam etika kerja MCW. Tiga larangan berikutnya muncul dalam kalimat-kalimat
93
spontan yang dilontarkan oleh aktor dengan pedagogic authority (PAu), yaitu
LJK, atau senior seperti Mas Sabbir, “Jadi biar merata ngomongnya di media,
nggak dimonopoli satu orang kayak dulu” atau “Jangan mau disuruh-suruh
mereka. Kalau mau ketemu ya ke sini dong. Apa itu,” kata LJK dengan mimik
yang agak marah ketika salah satu anggota Polresta Malang menelepon dan secara
informal meminta Zia—yang saat itu menjadi koordinator badan pekerja—untuk
datang ke Polresta. LJK sering sekali berkata demikian baik dalam suasana
bercanda dan serius. Ia selalu meminta badan pekerja tidak bersikap seolah-olah
aparatur negara selalu lebih tinggi.
Cara yang kedua adalah melakukan pengharusan-pengharusan untuk
menerapkan perilaku tertentu. Cara yang kedua ini dilakukan hanya dengan cara
spontan oleh aktor dengan PAu. Pengharusan-pengharusan spontan dalam
kegiatan itu meliputi sikap-sikap (a) berani menekan atau memarahi pemerintah;
(b) melakukan respon yang cepat (sesuatu) ketika rakyat berteriak (merasa
diperlakukan tidak adil) dan (c) membela pihak yang rentan atau lemah.
Cara yang ketiga adalah dengan menempatkan relawan dan badan pekerja
dalam kondisi-kondisi tertentu dalam suatu momen kegiatan dan memberi mereka
tanggung jawab. Momen kegiatan yang sering digunakan adalah kegiatan yang
berhubungan dengan advokasi. Misalnya, advokasi kasus modernisasi pasar
Dinoyo dan Blimbing. Rahim, yang saat itu menjabat kepala divisi pelayanan
publik dan baru bergabung sekitar dua bulan diserahi tanggung jawab untuk
mengkoordinir kegiatan-kegiatan advokasi dengan didampingi LJK. Ia selalu ikut
dalam rapat-rapat, menjadi contact person MCW untuk berhubungan dengan
94
pedagang pasar. Ia juga ikut mengorganisir aksi demonstrasi pedagang Dinoyo di
depan Balaikota. Penulis sendiri juga pernah mengalami pelibatan-pelibatan
semacam itu, misalnya saat MCW bersama-sama ke gedung dewan untuk
menemui anggota Komisi D pada tanggal 27 Juni 2011. Kami semua masuk ke
ruangan rapat Komisi D. Penulis didaulat sebagai juru bicara. Dengan penulis
menyatakan tuntutan untuk menghapus semua biaya sekolah SD dan SMP dan
biaya yang sudah terlanjur dibayarkan dikembalikan lagi kepada orang tua.
Kegagapan itu dikarenakan penulis sendiri belum yakin dengan tuntutan itu.
Pasal-pasal yang kami kumpulkan dalam surat tuntutan kami adalah pasal-pasal
yang mendukung pembebasan biaya pendidikan dasar. Padahal, penulis yakin
pasti ada pasal lain yang dipakai sebagai alat legitimasi sekolah untuk memungut
biaya. Bagi penulis, pasal itu perlu dilihat dulu untuk melihat masalah itu dengan
lebih baik lagi. Bahkan, hal itu juga bisa digunakan untuk memperkuat argumen
kami.
LJK kemudian yang berbicara banyak di dalam ruangan itu, berlandaskan
segala pengetahuan yang ia miliki dan pengalaman-pengalamannya yang dulu
dalam berdiskusi dengan dewan. Juga beberapa data pengaduan seadanya, tanpa
tertulis hanya lisan. Bahkan LJK berani menjamin ada buktinya, saat dewan
menanyakan. Yang dapat dilihat di sini adalah dengan data seadanya MCW maju
dan menekan pemerintah.50
Pengalaman lain juga dialami oleh Faruk. Ia ditelepon oleh seseorang yang
mengaku sebagai kepala sekolah dan ingin bertemu dengan MCW (yang saat itu
50 Catatan lapangan, 27 Juni 2011
95
berhubungan adalah divisi korupsi politik) untuk membicarakan kasus surat
edaran walikota, yang saat itu sedang hangat. MCW memprotes dikeluarkannya
surat edaran walikota yang menghimbau pemotongan gaji seluruh PNS di kota
Malang sebesar 2,5 persen untuk zakat, infaq, dan sedekah.
Di sinilah penulis melihat Faruk dididik untuk memiliki perilaku politik
tertentu oleh LJK. Seorang yang mengaku kepala sekolah itu belakangan
diketahui adalah orang suruhan seorang pejabat tinggi di kota Malang. Ia meminta
pertemuan itu dilangsungkan di Hotel Tugu, Malang. Bahkan, sempat juga
direncakan berpindah ke Hotel Taman Regent, Malang.
Namun, LJK mengatakan untuk tidak menuruti permintaan itu. “Kalau
mau ketemu, temui di kantor,” katanya. Alasannya, berbahaya kalau ingin
bertemu di hotel dan tertutup seperti itu. “Bilang saja, etika kerja kami tidak
memungkinkan kami untuk datang. Silahkan datang ke kantor,”
Bahkan, direncakan juga orang itu akan ‘dikerjai’ di kantor. Maksudnya,
ditakut-takuti. Sementara mereka bertemu Faruk, LJK dan teman-teman
Maduranya akan ada di luar ruangan sambil berbicara bahasa Madura—
diharapkan ini akan menakuti mereka. LJK kemudian bercerita bahwa ia juga
pernah ditawari uang segebok oleh seorang pejabat, dan ia tolak. Dan, ini tidak
hanya terjadi satu kali.51
LJK sering mengatakan bahwa semua kegiatan di MCW adalah sarana
belajar. Dan, dari sikap yang diambilnya, terlihat bahwa pelatihan secara sistemik
tidak menjadi hal yang utama untuk mengkader relawan. Kaderisasi memang
51 Catatan lapangan, Mei 2011
96
banyak dilakukan melalui pelibatan-pelibatan seperti yang telah dijelaskan di
atas.52
Cara yang keempat adalah melalui nasihat-nasihat yang diberikan oleh
LJK maupun orang lain yang dianggap senior. Misalnya pada bulan November
2010 (tangal tidak tercatat) Abdullah, salah satu badan pekerja Indonesia
Corruption Watch (ICW), berkunjung ke Malang untuk mempresentasikan
rencana riset. LJK mengajak badan pekerja dan relawan untuk berbincang
bersama Abdullah. Pada perbincangan ini LJK memperkenalkan badan pekerja
MCW dan relawan-relawan baru. Kemudian Abdullan berkata, “Wah, bagus ini.
Ada anak-anak muda yang mau berjuang bagi masyarakat. Jarang lho. Ini jelas
beda dengan apa yang dilakukan oleh aktivisme kampus. Kerjaannya apa nggak
jelas. Tapi kalian harus bertahan ya. Karena melakukan perjuangan ini nggak
mudah. Banyak tantangan, terutama pragmatisme. Kalo kena itu, wah, bahaya.”.
Lalu, ia menceritakan pengalaman seorang teman yang tidak bisa bertahan di
dalam pekerjaan di organisasi non-pemerintah. Setelah menceritakan itu, ia
kembali mendorong para relawan untuk bertahan.
Ada juga satu perbincangan yang terjadi pada tanggal 26 November 2010,
setelah rapat rutin Badan Pekerja selesai. Dalam kesempatan ini, LJK
menceritakan perjalanan hidup dan pergulatan batinnya sampai ia memilih untuk
menjadi orang yang mengkhususkan diri berjuang menguatkan masyarakat sipil
melalui organisasi non-pemerintah. Dalam perbincangan ini juga ia
mensosialisasikan ide atau nilai bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang
52 Salah satunya pernah diungkapkan oleh LJK pada tanggal 12 Oktober 2010 saat perbincangan informal yang terjadi di sela-sela rapat.
97
memberikan diri bagi sesama yang secara konkret bisa dilakukan dalam
perjuangan-perjuangan seperti yang dilakukan MCW.
Cara yang selanjutnya yang penulis amati adalah pengimposisian yang
monopolistis mengenai habitus/etika tertentu dalam diskusi-diskusi MCW. Dalam
diskusi-diskusi itu, “sisipan” imposisi etika tertentu selalu terjadi, tentunya
dilakukan oleh LJK sebagai aktor dengan PAu, misalnya seperti yang pernah
penulis amati pada saat acara diskusi tanggal 13 Juni 2011. Acara diskusi itu
dinisiasi oleh Hakim, Lutfi, dan Rusdiyanto. Diskusi itu semacam kelas yang akan
berlangsung tiap minggu, membicarakan tema ideologi, politik, dan pemerintahan.
Mereka sepakat mengadakan kelas itu karena berencana tidak pulang kampung
saat libur kuliah semester genap 2010/2011. Mereka meminta LJK untuk menjadi
pemateri.
Pertemuan dimulai pukul 19.21 WIB. LJK yang memulai menjelaskan
bahwa pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan program MCW. Ini adalah
inisiatif dari tiga orang tadi, dan menjadi forum tersendiri yang bukan bagian dari
capacity building MCW. Namun, penulis melihat bahwa ini tentu dimanfaatkan
juga sebagai sarana untuk mewariskan budaya politik.
Awalnya, memang LJK memberikan pengertian tentang ideologi. Slide
yang sudah disiapkan juga sepertinya memang bersifat akademis—mengajar,
bukan memprovokasi. Namun, pada akhirnya pertemuan ini juga menjadi sarana
imposisi budaya itu. LJK berkata,
“Politik itu hadir karena memberi kebajikan. Kalau masuk politik ya harus hadirkan kebajikan. Dalam konteks ini ide hadir...kekuasaan itu efektif
98
ketika kita ingin membangun kebajikan. Kekuasaan itu instrumen untuk hadirkan kebajikan. Sekarang kan dibalik.”53
Dan, ia juga berbicara mengenai ideologinya tentang kolektivitas,
“Kenapa Marx itu sangat luas dipakai? Karena Marx mampu membangun harapan. Apa slogannya? Kita ini sama-sama miskin, sama-sama ditindas negara, sekarang kita bisa rebut negara. Makanya ada land reform...Saya punya mimpi: segala sumber daya yang kita punya ini bisa kita nikmati bersama. Seperti perusahaan ini. Ini adalah bentuk kolektivisme. Kita punya mimpi.”54
Lalu, ia juga bercerita mengenai usaha tani, “Emang impas terus. Tapi
yang kami senang adalah Samsul nggak jadi buruh lagi. Dia jadi pemilik atas
tanahnya sendiri.”55
Dalam kesempatan yang lain penulis juga mengamati perbincangan
informal yang terjadi pada tanggal 29 April 2011. Didit memulai pembicaraan
dengan berkata, “Mas. Aku jadi kepikiran kata-katanya Mas Ichwan hari selasa
lalu. Kita ini elitis apa grassroot?”56 Lalu LJK menjawab bahwa non-goverment
organization (NGO) memang telah mengalami pergesaran. Dulu, NGO hadir
untuk mengawal kebijakan negara. Pasca ‘98, muncullah NGO-NGO yang hanya
dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan (menjadi kendaraan untuk mengambil
kekuasaan).
LJK kemudian juga berkata,
“Sebenarnya semua itu didasari pada kenginan kita untuk membentuk keadaban atau sivilitas. Ideologi adalah basis argumentasi kita. Dan, aktivis itu adalah mata air NGO. Perjuangan kita ini kan perjuangan politik, tapi politik nilai, bukan politik kekuasaan. Kalau kita jadi aktivis sosial, tapi kita tidak beradab kan susah. Masalah elitis atau tidak ya kita
53 Catatan lapangan, 13 Juni 2011 54 Ibid 55 Ibid 56 Maksudnya, apakah gerakan MCW itu bersifat elitis (yang hanya menyentuh kebijakan tingkat atas) atau juga menggerakkan masyarakat bawah
99
yang menjawab. Kalau memang keputusan teman-teman bahwa kita harus mengakar dalam gerakan grassroot, ya ke depan harus diatur bagaiamana. Apa saja yang harus kita lakukan. Apa saja yang menjadi pilihan-pilihan kita.”57
Kemudian LJK juga bercerita mengenai seorang ulama yang ia kagumi. Ia
adalah seorang ulama, tapi terlibat dalam gerakan-gerakan MCW. Ulama itu
sudah meninggal. LJK menceritakan semangatnya dan mengulang kata-katanya,
“Ngapain kita dakwahin orang yang sudah bener. Harusnya ya kita dakwah
kepada orang jahat.”58
Adapun karakteristik atau ideal aktivis sebagai nilai yang diimposisikan
secara monopolistis tersebut penulis temukan dalam baik dalam perbincangan-
perbincangan informal maupun dalam kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan
spontan sehari-hari. Hal-hal tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang harus
dimiliki oleh seorang aktivis, sebagaimana yang penulis cantumkan:
Tabel 8. Karakteristik Aktvis Menurut MCW59 Characteristics of Aktivis
1. Intelek 2. Visioner 3. Beradab/Bermartabat 4. Mampu mengorganisasi 5. Punya tujuan yang jelas dalam melakukan kegiatan 6. Mempunyai ide-ide segar 7. Mempunyai inisiatif 8. Militan 9. Uang bukan tujuan
Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Pertama, seorang aktivis haruslah intelek. Artinya, mampu menggunakan
kemampuan pikirannya untuk membaca fenomena dan merumuskan strategi yang 57 Catatan lapangan, 29 April 2011 58 Ibid 59 Lihat catatan kaki hal. 71 (no. 24)
100
diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang pernah diungkapkan LJK
saat diskusi tanggal 13 Juni 2011, “Akal kita harus kita pakai. Kita harus
berpikir.”
Aktivis juga harus visioner. LJK memaksudkan orang visioner sebagai
orang yang mempunyai impian jangka panjang terhadap pekerjaan-pekerjaan civil
society. Yang sering juga didengungkan adalah aktivis harus bermartabat dan
beradab. “Kerjaan kita ini kan membangun peradaban. Kalau kita sendiri nggak
beradab kan repot,”60. Istilah beradab sendiri tidak pernah dijelaskan secara
definitif, namun sering dipertukarkan dengan istilah bermora atau yang penulis
tangkap memiliki nilai-nilai luhur.
Karakteristik yang selanjutnya adalah mampu mengorganisasi. Ini tidaklah
menjadi hal yang terlalu penting dibandingkan tiga hal yang telah disebut di atas.
Mengorganisasi masyarakat bukanlah modal yang harus dimiliki sebelum
seseorang bergabung dengan MCW. Hal itu bisa dilatihkan setelah seseorang
bergabung dengan MCW. Meskipun demikian kemampuan mengorganisasi
sesuatu menjadi kemampuan yang sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya
pekerjaan advokasi yang dilakukan MCW.
Aktivis diharuskan juga memiliki tujuan yang jelas dalam berkegiatan
sehingga tidak menghamburkan sumber daya. Hal ini sering dikontraskan dengan
oknum-oknum pemerintahan yang melakukan kegiatan dengan menghamburkan
sumber daya dengan tujuan dan pencapaian yang tidak jelas. Berhubungan dengan
ini, seorang aktivis juga diharapkan memiliki ide-ide segar yang kreatif untuk
60 Perbincangan informal, Maret 2011
101
mengadakan kegiatan sebagai strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan
kemudian berinisiatif melakukannya.
Yang selanjutnya berhubungan dengan militansi. Militansi sering diartikan
sebagai komitmen waktu yang besar dan ketangguhan dalam mengerjakan tugas.
Ini menjadi hal yang penting untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan MCW.
Ukuran atas hal ini menjadi alat seleksi utama relawan sebelum dia diangkat
sebagai badan pekerja. Orang-orang yang bergabung di MCW dinilai berdasarlam
militansinya. Ini juga sering dilekatkan pada sikap yang tidak menjadikan uang
sebagai tujuan hidup, apalagi menggunakan aktivisme sebagai sarana untuk
mencari uang.
Cara yang selanjutnya yang penulis amati adalah training relawan. Bagi
anggota MCW, ini sering disebut-sebut sebagai sarana kaderisasi. Namun, penulis
melihat tanpa disadari training relawan hanyalah menjadi alat untuk menjaring
orang, bukan mendidik.
4.3. Budaya Politik MCW dan Reproduksinya
Dalam bagian ini, akan dipaparkan hasil analisis komponensial dan proses
penemuan cultural themes atau tema budaya. Seperti yang sudah diungkapkan di
Bab III, cultural themes adalah “sebuah postulat atau posisi, baik itu
dideklarasikan atau hanya terkandung secara implisit, dan biasanya memandu
perilaku atau menstimulasi aktivitas, yang secara tidak terlihat diterima atau
secara terbuka dipromosikan di dalam sebuah masyarakat” (Opler dalam
Spradley, 1980:140).
102
Postulat atau posisi itu berupa prinsip yang secara terus menerus muncul
dalam setiap domain budaya dan biasa berbentuk kalimat asertif. Maka, penulis
akan berusaha menemukan postulat apa yang mendasari perilaku politik MCW
dan bagaimana mereka melakukan reproduksi budaya itu. Analisis komponensial
yang disajikan dalam bentuk tabel paradigma akan membantu dalam hal
menemukan atribut budaya yang melekat pada dimensi kontras sehingga bisa
ditemukan prinsip-prinsip yang terus muncul dalam domain-domain budaya
sehingga dapat disimpulkan postulat atau posisi apa yang dipegang MCW.
4.3.1. Budaya Politik MCW
Tema budaya atau postulat yang mendasari segala aktivitas politik MCW
adalah bahwa semenjak kejatuhan Soeharto, demokrasi ‘dicuri’ oleh sekelompok
elit politik sehingga rakyat tetap tidak menikmati kesejahteraan. Maka,
sekelompok elit itu harus dilawan. Masyarakat yang haknya dirampas atau yang
dalam bahasa LJK ditipu, harus disadarkan untuk kemudian melawan.
Hal ini diketahui melalui wawancara penulis dengan LJK tanggal 9
Agustus 2011. Wawancara ini dilakukan untuk memastikan dimensi-dimensi
kontras yang telah penulis temukan dan jabarkan. Ini dilakukan untuk domain
budaya kinds of activities.
Untuk kinds of activities, penulis bertanya apakah memang dimensi
kontrasnya adalah prosedural dan non-prosedural. Ternyata, jawabannya tidak.
Lebih tepat litigasi, non-litigasi, terbuka dan tertutup. Ada yang melalui langkah
hukum (ikut prosedur hukum/birokrasi) ada yang tidak ikut prosedur
103
hukum/birokrasi, seperti pernyataan pers, legal opinion, legal anitation,dll.
Tentang terbuka dan tertutup, LJK mengatakan, “Ada yang perlu mengajak publik
bareng-bareng, ada yang cukup kita dengan pemerintah, untuk memberi
saran/masukan.”
Saat ditanya mengenai kontras di antaranya, jawaban yang muncul justru
adalah mengenai pilihan gerakan. Jadi cara-cara yang dipakai dalam berpolitik itu
menurutnya tergantung pada karakteristik dan ideologi gerakan. Karakteristik dan
ideologi gerakan akan memunculkan perilaku.
“Kalau ideologinya adalah konfrontatif, tentu pilihannya adalah
pelembagaan gerakan sosial. Bagaimana kita membangun gerakan sosial,” LJK
kemudian juga menkontraskan ideologi ‘kita’ (MCW) dengan ‘yang lain’ (tanpa
menyebut nama). Ia menyebut mereka yang lain itu pragmatis. Maksudnya,
menjadi partner pemerintah (DPRD) dalam legislative drafting; berteman supaya
idenya cepat diakomodasi. MCW, katanya, lebih dari itu. “Kita ini membangun
kesadaran publik,” katanya. Ia kemudian menjelaskan postulatnya bahwa ia yakin
bahwa semenjak jatuhnya Soeharto, ‘kran-kran’ telah terbuka. Namun, rakyat
menjadi gagap. Demokrasi kemudian hanya dikuasai oleh sekelompok elit. Atau
yang ia sebut sebagai ‘demokrasi poliarkhi’. Elit-elit ini membajak demokrasi
sehingga tercipta jurang antara mereka dengan rakyat. Tugas civil society adalah
menstimulasi kesadaran publik supaya mereka tidak gagap lagi. “Kita membawa
mereka sampai kepada kesadaran kritis,” katanya memakai istilah Paulo Freire,
supaya mereka tidak tertipu lagi.
104
“Jadi, yang tertipu-tertipu itu kita sadarkan, sampai mereka berkata, ‘Iyo
yo, selama iki awake dewe ditipu,’61 Lalu, kita kumpulin mereka-mereka ini untuk
membangun gerakan,” katanya. Tugas civil society adalah untuk menjembatani
jurang antara rakyat dengan elit melalui pendidikan publik supaya tidak ada lagi
jurang. “Bisa dikatakan bahwa kita ini sedang melakukan revolusi budaya.”
Jelas pula bahwa tujuan internal itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan
besar. “Ya, bener” kata LJK saat dikonfirmasi. LJK juga berbicara mengenai
model pecahnya sel amoeba dalam melakukan revolusi budaya ini. Ia berharap
nilai-nilai (tujuan membangun revolusi budaya) ini tertanam dalam diri alumni
MCW sehingga mereka bisa mengerjakan itu di sektor mereka.
Dari perbincangan tersebut, penulis memperbaiki kembali tabel paradigma
mengenai kinds of activities yang sebelum pernah dibuat dan mencoba melihat
konsep-konsep yang melekat padanya untuk menguatkan hasil wawancara di atas.
Selain itu, juga dalam rangka menguatkan hasil wawancara di atas pula, penulis
juga akan menyajikan analisis komponensial untuk domain-domain kinds of
politics dan kinds of goals, Dari tabel-tabel paradigma tersebut, ditemukan
beberapa konsep atau atribut budaya yang melekat pada dimensi-dimensi kontras
itu sebagaimana tersaji berikut:
Tabel 9. Tabel Paradigma Kinds of Activities
Domain
Dimension of Contrast Yang
terlibat Fasilitas Tujuan Litigasi/N
on-Litigasi
Terbuka/Tertutup
Intern/Ekstern
Rapat Konsultasi dan Pengorganis
Teman-teman seperjuangan
Seadanya Mengorganisasi gerakan
- Terbuka Intern
61 Bahasa Jawa, artinya: Iya ya, selama ini kita dibohongi.
105
asian Multistakeholder meeting
Obyek pantau dan teman-teman seperjuangan
Serius dipersiap-kan
Mempengaruhi pemerin-tah
Non-Litigasi
Terbuka Ekstern
Diskusi Publik
Obyek pantau dan teman-teman seperjuangan
Serius dipersiap-kan
Mempengaruhi pemerin-tah
Non-Litigasi
Terbuka Ekstern
Pertemuan Konsolidasi
Teman-teman seperjuangan
Seadanya Mengor-ganisasi gerakan
- Terbuka Intern
Aksi Demonstrasi
Teman-teman seperjuangan
Serius dipersiap-kan
Mempengaruhi kebijak-an
Non-litigasi
Terbuka Ekstern
Memberikan pernyataan pers yang keras
Anggota Badan Pekerja MCW
Sederhana Mempengaruhi kebijak-an
Non-litigasi
Tertutup Ekstern
Mendatangi DPRD dan memaksa bertemu
Badan Pekerja MCW dan teman-teman seperjuangan
Sederhana Mempengaruhi kebijak-an
Non-litigasi
Terbuka Ekstern
Berargumen Bada Pekerja MCW dan teman-teman seperjuangan
Sederhana Mempengaruhi kebijak-an
Non-litigasi
Tertutup Ekstern
Melayangkan surat pernyataan keberatan atas ditolaknya permohonan informasi
Badan Pekerja MCW
Yang diperlukan saja
Mempengaruhi kebijak-an
Litigasi Tertutup Ekstern
Melayangkan surat tuntutan yang
Badan Pekerja MCW dan
Yang diperlukan saja
Mempengaruhi kebijak-an
Non-Litigasi
Terbuka Ekstern
106
dilengkapi opini hukum
teman-teman seperjuangan yang membentuk koalisi
Melaporkan kepada kejaksaan
Badan Pekerja MCW dan teman-teman seperjuangan yang membentuk koalisi
Yang diperlukan saja
Mempengaruhi kebijak-an
Litigasi Tertutup Ekstern
Sumber: analisis pribadi hasil data lapangan
Pada Tabel 9, konsep yang tampak kuat dan menyatukan semua dimensi
kontras itu adalah Civil Society yang vis a vis atau merupakan entitas yang
berbeda dari negara. Pada dimensi kontras yang pertama, yaitu siapa yang terlibat
dalam aktivitas yang dilakukan (“yang terlibat”), ditemukan bahwa ada kegiatan
yang melibatkan teman-teman seperjuangan saja dan ada kegiatan yang
melibatkan baik teman-teman seperjuangan dan obyek pantau. Hal ini jelas
mencerminkan demarkasi yang tegas antara pihak-pihak yang tidak masuk dalam
struktur pemerintahan dan sepaham dengan MCW dengan pihak-pihak yang
masuk dalam struktur pemerintahan. Artinya, MCW menahbiskan dirinya dan
mereka yang dianggap teman-teman seperjuangan sebagai entitas yang terpisah
dari, bahkan berhadap-hadapan dengan pemerintah.
Dimensi-dimensi yang selanjutnya, yaitu bagaimana MCW menyediakan
fasilitas untuk kegiatan itu (“fasilitas”), tujuan spesifik dari masing-masing
kegiatan itu (“tujuan”), apakah itu termasuk litigasi atau termasuk non-litigasi
(“litigasi/non-litigasi”), apakah aktivitas itu merupakan aksi yang terbuka
mengajak dampingan atau merupakan diskusi terbatas dengan pemerintah
107
(“terbuka/tertutup”), dan apakah kegiatan itu cenderung berurusan hal-hal intern
atau ekstern kelompok perjuangan (“intern/ekstern”) memiliki komponen budaya
yang sama dengan dimensi kontras yang pertama.
Pembedaan fasilitas yang dipersiapkan saat pertemuan konsolidasi internal
dengan diskusi publik yang melibatkan pemerintah didasari oleh demarkasi yang
telah disebutkan di atas. Di sini bisa dilihat bagaimana berbedanya MCW
mempersiapkan fasilitas ketika ia bertemu dengan teman-teman seperjuangan,
media—yang beberapa dianggap sebagai teman seperjuangan namun tetap
diperlakukan sebagai wartawan profesional, dan pemerintah. Ketika
mempersiapkan fasilitas pertemuan dengan teman-teman seperjuangan, fasilitas
yang disedikan sangat sederhana. Selalu dilakukan di ruang rapat MCW,
konsumsi yang tersedia hanyalah gorengan dan kopi yang diwadahi dua poci
kecil. Meminumnya pun menggunakan sloki. Ketika bertemu dengan wartawan,
fasilitas ruangan dan konsumsi bisa sama, namun MCW lebih serius dalam
menyediakan data yang diperlukan wartawan. Berbeda lagi ketika MCW
mengadakan pertemuan dengan pemerintah. Tempat yang dipilih adalah tempat
yang memadahi (bersih, nyaman, lebih berkelas) lengkap dengan fasilitas
konsumsinya (misalnya di restoran). Visualisasi materi berupa power point dan
LCD Projector dipersiapkan juga dengan baik. Artinya, performance menjadi hal
yang sangat diperhatikan ketika MCW berhadapan dengan pemerintah. Ia tidak
boleh terlihat memalukan atau terlihat lemah. Hal ini dapat dilihat sebagai strategi
defensif, supaya MCW juga mempunyai nilai tawar yang tinggi ketika berhadapan
108
dengan pemerintah. Dari sini dapat dilihat bahwa MCW menahbiskan dirinya
sebagai entitas yang berhadapan dengan pemerintah.
Apakah tujuan aktivitas itu untuk mengorganisasikan gerakan secara
internal atau untuk membangun gerakan dalam rangka mempengaruhi pemerintah,
apakah itu memakai strategi litigasi atau non-litigasi, dan apakah itu merupakan
gerakan yang terbuka atau tertutup sebenarnya hanyalah perbedaan strategi
melakukan advokasi. Aktivitas-aktivitas itu memiliki komponen budaya yang
sama yang melekat pada mereka, yaitu strategi bagaimana civil society, khususnya
NGO, melakukan gerakan perubahan kebijakan dan penyadaran masyarakat.
Tabel 10. Tabel Paradigma Kinds of Politics
Domain Dimension of Contrast
Siapa yg melakukan Beradab? Tujuan Posisi
Kekuasaan Politik Nilai “Kita” (Aktivis
NGO) Ya Kemanusiaan/Kebajikan Sebagai
Instrumen Politik Kekuasaan
“Mereka (Politikus Praktis)
Tidak Kekuasaan Semata Sebagai Tujuan
Sumber: hasil analisis pribadi dari data lapangan
Sedangkan pada Tabel 10, yaitu Tabel Paradigma Kinds of Politics,
terdapat dimensi kontras mengenai siapa yang melakukan kegiatan politik nilai
dan siapa yang melakukan politik kekuasaan (“Siapa yang Melakukan”). Yang
melakukan politik nilai adalah “kita” (aktivis NGO) dan yang melakukan politik
kekuasaan adalah “mereka” (politikus praktis). Sekali lagi, ini mencerminkan
demarkasi antara civil society, yaitu “kita”, dengan “mereka”, yaitu politikus
praktis yang duduk di struktur pemerintahan. Pada tiga dimensi kontras yang lain
(kategori beradab/tidanya, tujuan, dan posisi kekuasaan), melekat komponen
budaya kebajikan atau kemanusiaan atau pemberadaban. MCW mengakui dirinya
109
adalah gerakan politik, namun dengan tujuan kebaikan sesama. Hal ini lebih jelas
lagi dalam tabel paradigma berikutnya.
Tabel 11. Tabel Paradigma Kinds of Goals
Domain Dimension of Contrast
Posisi Keterungkapan Alasan
Sifat
Eksternal Membangun peradaban Tujuan utama Tacit Filosofis/Abstrak Menciptakan masyarakat madani
Tujuan utama Tacit Filosofis/Abstrak
Menciptakan tatanan masyarakat yang adil
Tujuan utama Tacit Filosofis/Abstrak
Mengubah kebijakan yang merugikan
Tujuan utama Explicit Konkret
Menciptakan pelayanan publik yang baik
Tujuan utama Tacit Konkret
Memberi harapan pada jaringan
Tujuan utama Explicit Filosofis/Abstrak
Membangun blok politik
Tujuan utama Explicit Konkret
Internal Mendapatkan dana Alat untuk mencapai tujuan utama
Explicit Konkret
Memberi panggung dan memunculkan aktor-aktor baru
Alat untuk mencapai tujuan utama
Explicit Konkret
Mengkonsolidasi relawan
Alat untuk mencapai tujuan utama
Explicit Konkret
Mempertahankan relawan
Alat untuk mencapai tujuan utama
Explicit Konkret
Mendapatkan relawan Alat untuk mencapai tujuan utama
Expilicit Konkret
Meningkatkan kapasitas relawan
Alat untuk mencapai tujuan utama
Tacit Konkret
Menjadikan MCW lembaga yang kredibel
Alat untuk mencapai tujuan utama
Tacit Konkret
Menjadikan MCW lembaga yang dipercaya masyarakat
Alat untuk mencapai tujuan utama
Tacit Konkret
Membangun tradisi intelektual
Alat untuk mencapai tujuan utama
Explicit Konkret
Pribadi Dapat pahala Pendorong untuk mencapai tujuan internal
Tacit Konkret
110
dan eksternal Belajar Pendorong
untuk mencapai tujuan internal dan eksternal
Tacit Konkret
Masuk surga Pendorong untuk mencapai tujuan internal dan eksternal
Tacit Konkret
Berbuat baik Pendorong untuk mencapai tujuan internal dan eksternal
Tacit Filosofis/Abstrak
Membangun masa depan diri sendiri
Pendorong untuk mencapai tujuan internal dan eksternal
Tacit Filosofis/Abstrak
Sumber: analisis pribadi hasil data lapangan
Tabel 11, yaitu Tabel Paradigma Kinds of Goals terdiri dari 3 dimensi
kontras, yaitu posisi tujuan itu masing-masing terhadap satu sama lain (“posisi”),
apakah alasan bagi adanya tujuan itu tacit atau explicit (“keterungkapan alasan”),
dan apakah tujuan itu merupakan filosofi yang abstrak atau tujuan spesifik yang
konret (“bentuk”). Dari dimensi kontras yang pertama, diketahui bahwa bagi
MCW ada tujuan atau mimpi besar yang ingin dicapai dan ada “pekerjaan-
pekerjaan kecil” (istilah LJK) yang perlu dilakukan untuk mencapai mimpi besar.
Tujuan besar adalah tujuan utama. Tujuan-tujuan utama itu berkaitan dengan hal-
hal di luar MCW, sedangkan “pekerjaan kecil” itu adalah tujuan-tujuan yang
berkaitan dengan hal internal MCW. Walaupun tidak pernah diungkapkan secara
ekplisit, penulis juga melihat keberadaan tujuan pribadi yang menjadi pendorong
masing-masing relawan bergabung di MCW. Tujuan ini yang jarang sekali
dibahas di dalam perbincangan-perbincangan dengan LJK. Khususnya tujuan
“membangun masa depan pribadi”, ketika membicarakannya, relawan tidak
111
pernah melibatkan LJK dan terkesan sembunyi-sembunyi dan perasaan takut atau
malu membicarakannya secara terbuka, apalagi dengan LJK. Perbincangan
mengenai “pekerjaan kecil” pun kalah sering dengan perbincangan mengenai
tujuan utama MCW. Hal ini mencerminkan adanya suatu pagar dalam berperilaku
yang berhubungan prinsip altruisme dan egoisme. Bunyinya kira-kira: pengejaran
terhadap kepentingan atau keuntungan pribadi itu buruk, sedangkan pengejaran
terhadap tujuan utama itu mulia.
Dua dimensi kontras yang selanjutnya, yaitu “keterungkapan alasan” dan
“sifat” menjelaskan bahwa ada ide-ide tertentu yang taken for granted atau
menjadi suatu dasar yang tidak dipertanyakan lagi keniscayaannya baik itu
merupakan ide yang abstrak atau filosofis, maupun ide yang konkret. Tujuan-
tujuan utama yang alasannya bersifat tacit, berhubungan dengan ide besar
kemanusiaan yang mengingatkan kembali pada kinds of politics bahwa kegiatan-
kegiatan politik MCW ditujukan untuk kebajikan atau kebaikan manusia lain.
Muali dari yang paling abstrak, yaitu “membangun peradaban”, hingga yang
paling konkret untuk menjawab tujuan besar itu, yaitu “menciptakan pelayanan
publik yang baik”. Pada bagian tujuan internal, peningkatan kapasitas relawan,
usaha menjadikan MCW lembaga yang kredibel, dan usaha membuat MCW
dipercaya masyarakat adalah tujuan-tujuan yang alasannya tacit. Yang juga patut
mendapat perhatian adalah tujuan-tujuan religius yang ada pada masing-masing
relawan MCW. Selama keterlibatan penulis di sana, memang mereka adalah
orang-orang yang taat beragama, menganggap agama sebagai dasar kehidupan,
112
sehingga tujuan-tujuan seperti mendapat pahala dan masuk surga adalah hal yang
tidak dipertanyakan lagi.
Penulis juga melakukan analisis komponensial (dimensi kontras) domain-
domain budaya yang ada untuk menguatkan temuan cultural themes mengenai
budaya politik MCW.
Tabel 12. Tabel Paradigma Domain-Domain Budaya MCW
Domain-domain Dimensi Kontras
Posisi dalam gerakan Posisi dalam Imposisi budaya
Yang memiliki ide
Kinds of Politics Pilihan mainstream gerakan
Nilai yang diimposisikan
LJK
Kinds of Activities Strategi gerakan Sarana “belajar” LJK
Kinds of Goals
Eksternal Dasar gerakan; nilai Nilai yang diimposisikan
LJK
Internal “Pekerjaan kecil” dalam gerakan
- Relawan
Pribadi Pendorong pribadi - Relawan
Ways of Cultural Imposition Cara menanamkan nilai (tujuan besar) dalam diri relawan
Cara dalam mengimposisikan budaya
LJK
Characteristic of Activist Ideal orang-orang yang terlibat dalam gerakan
Nilai yang diimposisikan
LJK
Sumber: analisis pribadi hasil data lapangan
Mengenai cultural themes budaya politik MCW, yang diperhatikan dalam
tabel di atas adalah kolom dimensi kontras “Posisi dalam Gerakan”. Perbedaan-
perbedaan yang tercantum dalam kolom “Posisi dalam Gerakan” sebenarnya
mencerminkan sebuah pengetahuan dasar, bahwa tujuan-tujuan besar yang ingin
dicapai MCW adalah hal yang utama sedangkan domain-domain kinds of politics,
kinds of activities, ways of cultural imposition, dan characteristic of activist
adalah pendukungnya. Mereka berfungsi sebagai pilihan strategi untuk mencapai
tujuan besar, nilai-nilai yang harus dimiliki relawan untuk mencapai tujuan itu,
dan cara bagaimana menanamkan nilai-nilai itu ke dalam diri relawan supaya
113
tujuan besar itu tercapai. Artinya, MCW mempunyai komitmen terhadap sebuah
tujuan besar. Dengan kata lain, MCW adalah organisasi yang visioner.
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan postulat yang mendasari
gerakan politik MCW: Demokrasi telah dicuri oleh sekelompok elit, dan civil
society ada untuk merebutnya kembali bagi rakyat demi membangun peradaban.
Seperti yang terungkap dalam hasil wawancara dengan LJK di atas, MCW
menyadari bahwa pasca-kejatuhan Soeharto merupakan momen aktor lokal
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam demokrasi di tingkat lokal. Kesempatan
dan ruangnya begitu besar sehingga banyak yang memanfaatkannya. Fenomena
ini disebut Siti Zuhro sebagai pergeseran dari bureaucratic authoritarian menjadi
bureaucratic pluralism; bahwa jika dulu keputusan-keputusan politik di daerah
sangat ditentukan oleh pusat sehingga sedikit sekali ruang bagi aktor lokal untuk
mempengaruhinya, sekarang ruang-ruang untuk berpartisipasi dalam perpolitikan
daerah sangatlah besar. Dalam istilah LJK, ini fenomena ini disebut sebagai
terbukanya ‘kran-kran’.
Sayangnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian latar belakang,
banyak aktor lokal yang memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri dan
merugikan masyarakat. Di Provinsi Bangka-Belitung dan Banten, misalnya,
Erwiza Erman (2007) menemukan bahwa otonomi daerah dan pemekaran provinsi
khususnya di pulau Bangka dan Belitung ternyata menjadi peluang besar bagi
terbentuknya shadow-state; penguasa beraliansi dengan pengusaha timah untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi dan kekuasaan politik mereka dan akibatnya
terjadi pembiaran pelanggaran-pelanggaran seperti perusakan lingkungan.
114
Inilah yang dikatakan Syarif Hidayat (2007:33) sebagai fenomena di mana
elit masyarakat (societal actors) membangun jaringan informal dengan
penyelenggara pemerintah daerah (local state-actors) untuk keuntungan yang
hanya dinikmati oleh mereka. Dalam bahasa LJK, ini disebut ‘demokrasi yang
dicuri elit’. Selain itu, temuan Erwiza Erman (2007) di Provinsi Bangka Belitung
menyebutkan bahwa aktor LSM lemah, bahkan menjadi sekutu untuk memihak
kepentingan. Zuhro, et.al (2009:228-230) juga memberi kesimpulan bahwa aktor-
aktor civil society rentan; ada yang masih tergantung dengan pembiayaan
pemerintah sehingga tidak kritis dan ada pula yang tidak punya kekuatan politis
sehingga hanya dipanggil ke ranah pembuatan keputusan ketika diperlukan.
Kenyataan-kenyataan ‘pencurian’ demokrasi dan rentannya aktor civil
society inilah yang membuat MCW mengambil posisi sebagai aktor lokal non-
pemerintah untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik sehingga
masyarakat awam tidak dirugikan. Ia jelas menahbiskan dirinya sebagai entitas
yang berbeda dari negara; berhadapan dengan negara dan tidak tergantung dengan
pemerintah.
Rosyada, et al, (2003:242) menyebutkan perlunya penguatan masyarakat
(warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu
mengontrol kebijakan negara (policy of state) yang cenderung memposisikan
warga negara sebagai subjek yang lemah. Sebagai implikasinya, lembaga swadaya
masyarakat merupakan komponen yang penting dalam civil society. MCW
melihat dirinya sebagai aktor yang mengimbangi kebijakan negara supaya warga
negara tidak lagi berada dalam posisi yang lemah. Ia memperjuangkan nilai-nilai
115
ideal yang ada dalam civil society, seperti kemandirian, keterbukaan, dan
ketidaktergantungan pada kondisi materi. Sesuai dengan pemikiran Atkinson dan
Scurrah, (2009); Weller, (2005), MCW termasuk ke dalam salah entitas civil
society, yaitu non-goverment organization (NGO), yaaitu organisasi yang
terbentuk secara formal dan memiliki agenda keadilan sosial yang eksplisit.
Mengenai tujuan besar, dilihat bahwa komitmen MCW yang kuat terhadap
kemanusiaan memang ada hubungannya dengan ideal masyarakat madani,
mengingat memang ideologi Islam sangat mempengaruhi LJK sebagai aktor
dengan PAu di MCW. Ia sendiri mengaku bahwa ia memang dipengaruhi ideologi
HMI.62 Ideologi HMI sendiri mencerminkan budaya kaum modernis Islam yang
terbagi menjadi dua, yaitu yang formalis dan yang substansialis (Prasetyo, et al,
2002:240-241). MCW sendiri lebih cenderung kepada yang keuda, yang
memandang bahwa penerapan kesempurnaan agama Islam itu lebih dengan
menanamkan nilai-nilai Islami di masyarakat, bukan dengan secara formal ingin
mengideologisasikan Islam atau mengetengahkan simbol-simbol Islam di dalam
masyarakat; menekankan pemisahan antara agama dan negara; antara wilayah
Tuhan dan manusia; antara yang transedental dan temporal. Mereka juga
menekankan pentingnya umat Islam berjuang bukan hanya bagi kepentingan
orang beragama Islam, tetapi juga kebutuhan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan. Hal ini dapat terangkum dalam ideal Nurcholis Madjid tentang civil
society yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani, yaitu kehidupan yang
62 Perbincangan informal tanggal 3 Mei 2011.
116
berkualitas, di mana tidak ada pihak yang memaksakan kehendaknya dengan
kemauannya sendiri (Madjid, dalam Prasetyo, et al, 2002:174).
Mengenai sikap perlawanannya terhadap negara, MCW mengingatkan
kembali akan gagasan kaum nasionalis-sekuler tentang bagaimana bernegara yang
baik, sesuai dengan penelitian Ramage (1995). Mereka berkeinginan mendorong
demokratisasi yang lebih baik, yaitu jalan atau perubahan dari rezim non-
demokratis menjadi rezim demokratis, yang mensyaratkan hadirnya kekuatan-
kekuatan penekan yang teroganisir dan relatif mandiri dari kontrol negara, yang
merupakan bagian dari civil society (Zuhro, et al, 2009:xviii,16). Dengan kata
lain, mereka berjuang untuk pemerintahan yang bersih dan baik (good
governance), sebagai salah satu tujuan demokrasi.
4.3.2. Reproduksi Budaya Politik MCW
Berikut akan dipaparkan bagaimana logika Pierre Bourdieu menjelaskan
fenomena reproduksi budaya politk di Malang Corruption Watch.
a. Pelibatan dan Perbincangan: Kerja Pedagogis MCW
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, reproduksi budaya adalah pewarisan
modal budaya, yaitu habitus kepada generasi selanjutnya. Habitus sendiri adalah
sistem karakter yang tahan lama atau dengan kata lain ia merupakan kebiasaan
berpikir dan bertindak yang mendarah daging. Proses pewarisan itu disebut
pedagogic work (PW), yaitu proses pengajaran atau penanaman nilai yang
berlangsung dalam jangka panjang untuk memproduksi habitus (Bourdieu dan
117
Passeron, dalam Jenkins, 1992:67). PW dilakukan dengan dua cara, yaitu implisit
dan eksplisit (Jenkins, 1992:68). Yang dimaksud implisit adalah proses
penanaman prinsip yang secara tidak sadar dilakukan yang nyata hanya dalam
praktek-praktek. Yang dimaksud eksplisit adalah proses penanaman yang secara
metode terorganisir, bahkan diformulasikan dalam prinsip-prinsip.
Kenyataan ini juga tampak dalam analisis komponensial terhadap domain
ways of cultural imposition.
Tabel 13. Tabel Paradigma Ways of Cultural Imposition
Domain Dimension of Contrast
Tertulis Yang melakukan
Frekuensi Dilakukan
Momen Dilakukan
Adanya tujuan laten
Pemagaran tertentu thd
perilaku
Etika kerja yang tertulis
Ya - - - -
Kalimat-kalimat spontan
Tidak Aktor dgn PAu dan BP
Sering Spontan -
Pengharusan-pengharusan tertentu
Tidak Aktor dengan PAu dan BP
Sering Spontan -
Pengkondisian-
pengkondisian tertentu
Diberi tanggung jawab tertentu dalam aktivitas politik
Tidak Aktor dengan PAu dan BP
Sering Terencana -
Dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas politik
Tidak Aktor dengan PAu dan BP
Sering Spontan dan Terencana
-
Pemberian nasihat Tidak Aktor dengan PAu
Sering Spontan -
Pengimposisian yang monopolistis mengenai habitus/etika tertentu dalam diskusi dan ceramah
Tidak Aktor dengan PAu
Jarang Spontan Mengimposisikan budaya, bukan berdialektika
Training Relawan Ya Aktor dengan PAu dan BP
Sangat jarang
Terencana Hanya menjaring, bukan imposisi
Sumber: analisis pribadi hasil data lapangan
118
Ada beberapa dimensi kontras dalam domain ways of cultural imposition,
yaitu apakah nilai-nilai itu disampaikan dan disepakati secara tertulis atau tidak
(“tertulis”), apakah itu dilakukan oleh aktor dengan PAu saja atau dilakukan juga
oleh badan pekerja lainnya (“yang melakukan”), apakah dilakukan dengan
terencana atau dalam momen yang spontan (“momen dilakukan”), dan apakah hal
itu merupakan tujuan dari kegiatan yang dilakukan atau tujuan laten (“adanya
tujuan laten”).
Dimensi yang pertama menunjukkan bahwa ada imposisi nilai yang
tertulis dan ada yang tidak. Penulis mengamati bahwa yang tertulis dan tidak
tertulis sama kuatnya. Mereka sama-sama punya kekuatan untuk memagari dan
mengharuskan perilaku tertentu. Yang tertulis lebih berfungsi sebagai
pengunguman kepada khalayak tentang etika kerja MCW. Mengenai dimensi
yang kedua, tidak ada aturan-aturan eksplisit mengenai cara imposisi mana yang
bisa dilakukan oleh badan pekerja dan aktor dengan PAu atau hanya boleh
dilakukan oleh aktor dengan PAu saja. Secara spontan komunitas MCW lebih
memberi kesempatan pada LJK sebagai aktor dengan PAu untuk leluasa
menyampaikan nasihat, pengharusan-pengharusan, dan pelarangan-pelarangan
terhadap perilaku. Sekalipun badan pekerja mempunyai kesempatan untuk
melakukan pemagaran, pengharusan, dan pengkondisian, mereka tetap
menempatkan dirinya di pinggir ketika LJK ada. Apalagi dalam cara imposisi
nasihat dan monopoli habitus tertentu dalam sebuah diskusi, badan pekerja tidak
pernah melakukannya.
119
Dimensi ketiga, mengenai perbandingan frekuensi masing-masing cara
imposisi, menunjukkan di cara mana MCW meletakkan perhatian atau usaha yang
lebih. Dari keterangan pada Tabel 10 di atas, diketahui bahwa pengharusan dan
pemagaran terhadap perilaku, pengkondisian, dan pemberian nasihat adalah hal-
hal atau cara-cara imposisi budaya yang sering dilakukan dibandingkan dengan
imposisi habitus di dalam diskusi dan training relawan. Artinya, cara-cara
imposisi yang informal, atau yang dalam istilah Bourdieu disebut implisit,
menjadi hal yang dominan dibandingkan dengan cara imposisi yang eksplisit.
Dimensi yang keempat memperbandingkan cara-cara mana yang dilakukan secara
spontan dan cara-cara mana yang dilakukan dengan terencana. Ditemukan bahwa
banyak yang dilakukan secara spontan. Sekali lagi, ini menunjukkan karakter
pedagogis implisit sebagi ciri kerja pedagogis MCW. Bahkan, cara-cara yang
termasuk dalam pedagogis yang eksplisit, seperti diskusi dan training relawan
malah mempunyai tujuan laten. Training relawan lebih merupakan usaha
penjaringan orang daripada praktik imposisi budaya. Diskusi yang seharusnya
merupakan sarana peningkatan skill relawan malah sering digunakan untuk
mengimposisikan habitus tertentu secara monopolistis. Habitus tertentu itu berupa
karakteristik aktivis. (lihat Tabel 4).
Hal ini juga tampak ketika penulis berbincang dengan Uni pada tanggal 13
Agustus 2011. Saat Uni ditanya mengenai apa yang membuatnya ingin terlibat di
MCW, ia menjawab, “Karena mimpi.” Dan ketika penulis bertanya mimpi apa
yang ia sedang tuju, ia menjawab, “Ya Indonesia yang lebih baik. Atau Malang
lah,” Ia melihat bahwa MCW lah yang bisa menjadi sarana untuk membangun
120
mimpi itu. Ia kecewa dengan teman-teman mahasiswanya karena menurut dia
tidak ada mahasiswa yang mempunyai mimpi itu. Semuanya terlalu peduli dengan
mimpi-mimpi atau ambisi pribadinya, misalnya kuliah di luar negeri.
Sepertinya nilai altruisme sangat melekat pada diri Uni. Ia
mempertentangkan mimpi bersama dengan mimpi pribadi ini. Seperti yang sudah
dibahas sebelumnya, pagar ‘tujuan pribadi itu buruk, tujuan bersama itu baik’
terlihat di sini. Ia melihat MCW lah yang membawa mimpi untuk Indonesia.
Teman-teman mahasiswanya tidak.
Lalu, saat ditanya apa yang dilakukan MCW untuk mencapai mimpi
Indonesia yang lebih baik itu, Uni menjawab bahwa caranya adalah dengan
membangunkan rakyat. Ia melihat bahwa rakyat sedang tidur. Mereka tidak sadar
bahwa mereka butuh bergerak; bahwa keadaan mereka sedang miskin, bodoh, dan
tertipu. Ia mengatakan,
“Masa mereka mau miskin terus? Mau bodoh terus? Tau nggak, orang Malaysia bilang orang Indonesia itu seperti apa? 3D. Dangerous, Dirty, and Disgusting.63 Mereka juga tertipu, pak. Disuruh bayar ini, bayar itu, tapi nggak tahu yang makan uang itu siapa.”64
Uni mengaku bahwa ia mendapatkan mimpi itu dari perbincangan dengan
LJK. Awal bergabung, ia berharap MCW bisa menjadi tempat untuk mewujudkan
mimpi ‘Indonesia lebih baik’-nya. Setelah bergabung, ia masih belum melihat
MCW sebagai tempat untuk membangun mimpi ‘Indonesia lebih baik,’. Namun
setelah mengalami perbincangan informal dengan LJK, ia paham bahwa MCW
bisa mewujudkan itu karena MCW punya tujuan besar menyadarkan publik. Uni
mengaku kaget bahwa ternyata pekerjaan MCW tidak hanya sebatas aktivitas- 63 Artinya: berbahaya, kotor, dan menjijikkan. 64 Catatan hasil wawancara, 13 Agustus 2011
121
aktivitas politik yang selama ini dilakukan. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu
membangun kesadaran masyarakat tadi. Ia mengatakan bahwa dari perbincangan
informal inilah ia menangkap mimpi itu. Bukan dari diskusi formal. Ini semakin
menguatkan bahwa memang pewarisan budaya atau Pedagogic Work itu
kebanyakan dilakukan secara implicit.
Ada juga relawan yang tidak memiliki dasar altruisme ketika bergabung
dengan MCW. Namun, itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk dibicarakan
secara terbuka di MCW. Hal semacam ini baru bisa diketahui ketika berbincang
secara pribadi, seperti yang penulis lakukan dengan Rusdiyanto pada tanggal 13
Agustus 2011, di kesempatan yang berbeda dengan Uni.
Saat ditanya apa yang membuatnya bergabung di MCW, Rusdiyanto
menjawab bahwa ia senang berpolitik dan ingin belajar bagaimana berpolitik itu
di MCW. Ia juga kecewa dengan organisasi ekstra kampus karena menurut dia
kegiatannya kurang menantang. Pekerjaan mereka hanya mengadakan acara-
acara, seperti pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di sekolah
menengah atas. Saat ditanyakan apakah tujuan itu sudah tercapai, ia menjawab
bahwa masih jauh untuk sampai kepada tujuan itu. Namun, sudah banyak
pengalaman baru yang ia dapatkan. Ia sudah merasakan manfaatnya dan
menyebutkan dua hal besar yang sudah ia pelajari. Pertama, tentang pemerintahan.
Ia belajar bagaimana sistem pemerintahan itu. Ia juga belajar mengenai korupsi;
bagaimana menangani kasus, di mana saja titik rawan korupsi, di mana akar
masalah korupsi. Kemudian, mengenai diri, ia mengaku bahwa ia terlatih
mentalnya; bagaimana berani memperjuangkan hak sendiri, bagaimana
122
berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan. Ia mengaku juga bahwa ia
belajar meningkatkan kapasitas; belajar disiplin membaca shingga ia mengaku
mengalami perubahan dalam hal pengetahuan. Maksudnya, pengetahuannya
bertambah. Ia terpacu setelah merasa dirinya tertinggal teman-teman yang
lainnnya dan sekarang merasa sudah mulai setara.
Kemudian penulis bertanya mengenai apa tujuan MCW ada. Ia menjawab
yang pertama adalah menciptakan pemerintahan yang baik sehingga bebas
korupsi. Ia memperiodesasikan pengetahuannya mengenai tujuan MCW. Pada
saat pertama masuk, ia melihat bahwa MCW adalah organisasi anti-korupsi,
politik, dan pengawas pemerintahan. Ia mengetahui hal itu dari brosur MCW.
Kemudian, setelah masuk, ia juga tahu bahwa ternyata MCW bertujuan
menyadarkan masyarakat. Ia mengetahui hal itu dari perbincangan informal
dengan LJK.
Lalu ditanyakan bagaimana dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan; apa
saja yang sudah ia pelajari. Ia menjawab bahwa dengan aktivitas-aktivitas itu, ia
bisa mengetahui kondisi lapangan. “Misalnya, ternyata masyarakat itu sudah agak
tahu daya kritisnya.” Setelah ditanya apakah ada kaitan antara aktivitas-aktivitas
itu dengan obrolan-obrolan dengan LJK, ia menjawab ada kaitannya. “Ngobrol itu
seperti dikasih materi, Mas. Lalu kita implementasikan di lapangan.” Hal ini juga
semakin menguatkan temuan bahwa kerja pedagogis yang dilakukan MCW
adalah pedagogis implisit.
Salah satu pemikiran Bourdieu mengenai reproduksi budaya adalah
konsekuensi logisnya, yaitu terjadinya reproduksi sosial. Dalam praktek
123
pengimposisian budaya di MCW, akan ada anggota yang merasa nyaman (feel at
home) dan ada yang tidak. Hal ini bisa disebabkan karena proses pedagogis yang
berbeda yang telah dialami masing-masing relawan sebelum ia bergabung di
MCW sehingga mereka memiliki habitus yang berbeda. Mereka yang tidak bisa
dan tidak mau menyesuaikan habitus mereka dengan habitus yang diimposisikan
MCW akan merasa tidak nyaman dan pada akhirnya tidak bertahan lama di
MCW.
Dua orang relawan yang sama-sama menjalani in-house training bersama
penulis menjadi contoh atas pengalaman ini. Sekalipun sudah menjalani in-house
training dan menjalani aktivitas-aktivitas di MCW, dua orang itu tetap merasa
tidak nyaman. Yang satu sejak kecil memiliki dibekali dengan pengetahuan
bahwa supaya hidup aman, lebih baik bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Orang tuanya tidak setuju dengan aktivitasnya di MCW. Mereka berpandangan
bahwa relawan ini seharusnya kuliah dengan baik, bisa lulus, dan kemudian
bekerja sebagai PNS. Tampaknya cara berpikir itu telah menjadi habitus-nya
sehingga ia tidak merasa nyaman dengan kerja-kerja MCW yang selalu
berkonfrontasi dengan pemerintah. Ketika ia harus mengirim surat kepada
pemerintah, ia menyingkat namanya dengan format singkatan yang berbeda dari
biasanya. Alasannya, ia tidak ingin diketahui orang tuanya bahwa ia
berkonfrontasi dengan pemerintah. Pada bulan Juli, akhirnya ia memutuskan
untuk tidak lagi menjadi badan pekerja dan berkata hanya sanggup memberikan
tenaganya sebagai relawan.
124
Seorang relawan yang lain memiliki habitus yang tidak cocok dengan
kerja-kerja dan mimpi besar MCW. Ia seorang aktivis mahasiswa yang lebih
menyukai kegiatan-kegiatan berdiskusi, ngobrol, dan sangat tidak terbiasa dengan
deadline dan pekerjaan-pekerjaan teknis. Ia sangat kesulitan mengikuti ritme kerja
MCW. Akhirnya, ia mundur pelan-pelan. Selain dua orang yang mengikuti in-
house training, penulis juga mengamati dua orang yang juga tidak aktif lagi di
MCW. Keduanya adalah aktivis organisasi ekstra kampus. Awalnya tiga orang ini
aktif dalam kegiatan-kegiatan MCW. Namun, setelah mengetahui kondisi kerja
dan peminggiran ide politik praktis yang sering dilakukan di MCW, penulis mulai
melihat ketidaknyamanan dalam diri mereka. Dua orang kemudian tidak pernah
menampakkan diri lagi. Yang satu kemudian mencalonkan diri sebagai ketua
Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus, yang satu bergabung dengan organisasi
politik praktis.
Dalam perspektif Bourdieu, di sinilah kesenjangan kesenjangan kelas
terjadi. Bourdieu berpendapat bahwa sistem imposisi itu menyembunyikan
privilise dengan mengabaikannya. Sering muncul kalimat dari LJK yang
mengatakan bahwa siapa saja dapat bergabung dengan MCW, asal bisa bertahan.
Benar memang, bahwa MCW terbuka bagi siapa pun untuk bergabung, asal ia
bukan anggota partai atau obyek pantau. Mereka seakan-akan memperlakukan
setiap orang sama. Padahal, relawan yang bergabung dengan MCW memulai
dengan ‘modal’ (habitus) yang berbeda. Mereka yang habitus-nya tidak sesuai,
tidak pernah dikeluarkan dari MCW. Namun, mereka merasa tidak nyaman
sehingga tereksklusi dengan sendirinya tanpa harus dieksklusi. Inilah yang disebut
125
dengan reproduksi sosial, yaitu reproduksi relasi di antara kelompok-kelompok
atau kelas-kelas (Bourdieu, 1990:54). Stratifikasi sosial atau kelas akan tetap ada
karena praktek pengimposisian budaya dalam suatu institusi akan menyebabkan
orang-orang yang tidak memiliki habitus yang sesuai akan dengan sendirinya
tereksklusi dan pada akhirnya tidak bisa menjadi bagian dari kelas tersebut.
b. LJK: aktor yang memiliki Pedagogic Authority (PAu)
Bahwa LJK merupakan aktor yang mempunyai otoritas pedagogis adalah
hal yang penulis amati menjadi pengetahuan dasar baik LJK sendiri maupun
relawan MCW dalam beraktivitas dan belajar di MCW. Ini tampak dari
pengamatan-pengamatan yang dilakukan, seperti yang sudah dipaparkan dalam
bagian analisis domain dan taksonomi, bahwa yang selalu memberikan nasihat
kepada relawan adalah LJK.
Kenyataan ini tampak dari analisis komponensial terhadap domain-domain
budaya yang ditemukan. Tabel ini sudah disajikan dalam bagian sebelumnya,
namun dengan fokus perhatian berbeda (lihat Tabel 11). Yang perlu diperhatikan
kali ini adalah dimensi kontras ‘Posisi dalam Imposisi Budaya’ dan ‘Yang
memiliki Ide’. Semua domain budaya itu ketika dilihat dalam kolom dimensi
‘Posisi dalam Imposisi Budaya’ hanya terbagi menjadi dua, yaitu yang berfungsi
sebagai nilai yang diimposisikan dan yang berfungsi sebagai cara bagaimana
suatu nilai diimposisikan. Kinds of Politics, Kinds of Goals (External), dan
Characteristic of Activist adalah domain-domain budaya yang berfungsi sebagai
nilai yang diimposisikan, sedangkan domain Kinds of Activities dan Ways of
126
Cultural Imposition berfungsi sebagai alat atau cara bagaimana nilai-nilai budaya
politik MCW diimposisikan.
Dari tujuh taksonomi atau domain budaya itu, hanya dua wilayah di mana
relawan memiliki idenya sendiri, yaitu Kinds of Goals yang internal, dan Kinds of
Goals yang pribadi. Domain-domain itu juga hanya terbatas pada tujuan pribadi
dan internal, atau yang disebut LJK sebagai “pekerjaan kecil”. Sedangkan domain
Kinds of goals yang eksternal, Kinds of Politics, Kinds of Activities, Ways of
Cultural Imposition, dan Characteristic of Activist idenya semua dimiliki oleh
LJK. Dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan
politik MCW, LJK-lah pemilik idenya. Bisa dikatakan bahwa ialah penentu
gerakan MCW.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, LJK adalah seorang aktor yang
memiliki pedagogic authority (PAu), yaitu kekuasaan untuk bertindak, yang
dialami sebagai sesuatu yang sah oleh penerima perlakuan itu. Tindakan yang
dilakukan oleh agen dengan PAu akan dialami sebagai sesuatu yang positif bagi
orang-orang yang menerimanya. Hampir seperti hubungan orang tua dengan anak.
Ia dianggap sebagai ‘mandated representative’ dari kelompok yang
mengimposisikan sebuah kultur. (Jenkins, 1992:66), atau seseorang yang
dianggap memiliki mandat dari kelompok itu. Penulis mengamati bahwa memang
seakan-akan semua anggota MCW ataupun orang-orang yang terlibat di MCW
memandatkan kuasa kepada LJK untuk menentukan arah gerak MCW.
Kekuasaan inilah yang membuat ia dianggap sah melakukan pedagogic
work (PW) sehingga ia juga menjadi aktor yang sebagian besar melakukan
127
imposisi budaya ke dalam diri relawan MCW. Penulis melihat bahwa ia dan
teman-teman sama-sama menyadari dan menyepakati posisi ini. Ketika LJK
melakukan imposisi budaya melalui nasihat-nasihat dan perbincangan informal,
bahkan meluai penyisipan-penyisipan itu dalam diskusi, tidak ada relawan yang
menentangnya. Semua nilai-nilai yang diungkapkan dianggap sah. Bahkan, seperti
yang sudah dijelaskan dalam analisis komponensial kinds of goals, relawan-
relawan cenderung malu dan tertutup membicarakan hal-hal yang tidak sesuai
dengan nilai yang sedang diimposisikan LJK, misalnya tujuan-tujuan pribadi
mereka, terutama yang berkaitan dengan membangun masa depan mereka sendiri.
Perbincangan dalam konteks wawancara yang penulis lakukan dengan
Rusdiyanto dan Uni pada kesempatan yang terpisah pada tanggal 13 Agustus
2011 juga mengkonfirmasi temuan di atas. Rusdiyanto mengakui bahwa MCW
masih banyak tergantung dengan LJK. Saat ditanya mengapa, ia mengatakan
karena kapasitas teman-teman sendiri, termasuk Didit belum cukup untuk
memimpin MCW. Uni bahkan mengaku bahwa LJK sendiri yang mengatakan
bahwa MCW itu masih tergantung padanya. Dalam perbincangan yang diikuti Uni
tanggal 12 Agustus 2011, LJK mengungkapkan pada relawan bahwa MCW masih
tergantung pada LJK. “Badan Pekerja MCW yang sekarang masih belum
mempunyai kapasitasnya sendiri,” kata Uni menceritakan. LJK menceritakan
bahwa pengurus Radio Republik Indonesia (RRI) yang saat itu meminta LJK
menjadi narasumber berpendapat bahwa kapasitas badan pekerja MCW yang
sekarang masih belum mumpuni. Terbukti mereka memaksa LJK yang hadir
128
dalam diskusi dengan seorang pejabat. Padahal, LJK sudah mencoba mengalihkan
kepada badan pekerja (kepada Didit, misalnya).
Modal simbolik yang begitu kuat sebenarnya adalah hasil menangnya
seseorang dalam kompetisi atas kontrol terhadap orang lain yang menempati
ranah tersebut.65 Bourdieu (1991:205) menyebutkan bahwa dalam politik, ada
pemberi mandat (mandant) dan ada penerima mandat (mandataire). Penerima
mandat memiliki otoritas dan legitimasi untuk berbicara atas nama kelompok
yang memberinya mandat. Mandat ini diterima karena penerima mandat
sebelumnya ‘menjajakan’ produk politiknya kepada pemberi mandat. Produk
politik itu misalnya program politik, slogan, logo, atau apa pun yang berisi aneka
wacana yang dapat memperkuat posisinya dalam ranah politik. Bourdieu (1991:
192-197) menyebutkan bahwa bila produk politik itu laku, maka agen politik
profesional yang menjualnya akan memperoleh kredit atau modal politik. Proses
jual beli inilah yang pada dasarnya adalah kompetisi atas kontrol terhadap
pemberi mandat (Bourdieu, 1991:190). Otoritas dan legitimiasi untuk berbicara
atas nama kelompok yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dapat
disebut sebagai modal simbolik.
MCW memang bukan ranah pertarungan politik dalam arti sempit.
Namun, di sana juga ditemukan fenomena bagaimana kelompok MCW
memberikan ‘kredit simbolik’ kepada LJK sehingga ia mempunyai modal
simbolik yang besar. Memang, LJK maupun Zia, atau Didit tidak secara sengaja
melakukan ‘penjajaan’ produk politik. Namun, apa yang mereka lakukan dinilai 65 Ranah sendiri diumpamakan oleh Bourdieu sebagai tempat bermain untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi. Lihat Allan, K. 2006. Contemporary Social and Sociological Theory. California: Pine Forge Press. Hal. 171-172
129
oleh orang-orang yang ada di dalam MCW, yaitu orang-orang yang memberi
mandat untuk menentukan siapa yang berhak berbicara atas nama mereka. Lebih
dari itu, mandat itu juga memberikan otoritas pedagogis, yang memberikan
seseorang kuasa untuk bertindak, di mana tindakan itu dialami sebagai sesuatu
yang sah. Orang-orang yang berada di MCW juga tidak secara sengaja ‘membeli’
produk politik. Mereka secara otomatis memberikan kredit simbolik kepada
seseorang yang dianggap berhak; sebagaimana yang diungkapkan Ayu, seorang
anggota badan pekerja MCW,
“Ya iyalah. Waktu Didit aja dikit-dikit kita ini ke Mas Luthfi. Secara nggak sadar, kita ini membesarkan nama Mas Luthfi. Kayak misalnya waktu kita telepon wartawan, kitakan bilang, ‘nanti ada Mas Luthfi kok,’ MCW dari dasarnya emang udah dari Mas Luthfi karena dia pendiri. Lihat aja, kalau LJK ngundang wartawan, pasti banyak yang dateng. Kalau kita?”66
Seperti yang telah diungkapkan di atas, LJK memang tidak melakukan
‘penjajaan produk’. Namun, apa yang melekat pada dirinya secara otomatis
membuat anggota MCW yang lain memberi kredit simbolik padanya. Yang
melekat pada dirinya itu adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dielakkan
bahwa ia adalah pendiri MCW—satu-satunya pendiri yang ada di MCW saat ini.
Kenyataan bahwa LJK adalah pendiri MCW memberikan kredit yang tidak
mungkin dimiliki Zia ataupun Didit sekalipun mereka memiliki jabatan struktural
eksekutif tertinggi di MCW. Yang sah memberikan petunjuk, arahan, dan
keputusan krusial adalah pendiri. Ini adalah keyakinan yang secara tidak disadari
dipegang oleh orang-orang yang berada di MCW.
66 Wawancara tanggal 20 September 2011
130
Selain status kesejarahannya sebagai pendiri, dua hal lain yang melekat
pada diri LJK, yang memberikan kepadanya kredit simbolik lagi adalah
pengalamannya yang lebih dari anggota badan pekerja dalam melakukan deskripsi
tugas MCW dan disposisi atau habitus-nya. Mengenai pengalaman dalam
melakukan deskripsi tugas MCW, tentu LJK jauh lebih berpengalaman. Selain ia
lebih dulu hidup 20 tahun dibandingkan anggota badan pekerja yang sekarang,
atau setidaknya 10 tahun dari anggota badan pekerja periode lalu, kenyataan
bahwa ia telah lebih dahulu melakukan kerja-kerja MCW sebelum anggota badan
pekerja yang baru ini masuk, menjadikannya orang yang paling berpengalaman di
MCW sehingga selalu menjadi rujukan anggota lain dalam bertindak.
Habitus LJK adalah habitus yang paling sesuai dengan habitus yang
sedang diimposisikan di MCW—tentunya karena ia sendiri yang
mengimposisikan habitus tersebut. Istilah yang sering disebut oleh anggota MCW
untuk menunjuk hal ini adalah ‘konsisten’. Ketika LJK mendorong anggota MCW
untuk memberikan waktu dan tenaga yang maksimal bagi MCW, ia terlebih
dahulu sudah melakukannya. Ketika ia mendorong anggota MCW untuk bersikap
intelek, ia sudah melakukannya. Ia telah menulis beberapa buku (yang
menurutnya adalah salah satu ciri intelektual), ia telah banyak berkecimpung
dalam kerja-kerja pengawasan pemerintah sehingga memiliki pengetahuan untuk
melakukan kerja-kerja tersebut secara ‘intelek’ (tidak melakukan kekerasan, tidak
mengeluarkan pernyataan yang kasar). Ketika ia mengatakan bahwa seorang
aktivits haruslah visioner, ia telah memiliki sifat itu—terbukti dengan dirinya
yang mendirikan MCW. Ketika ia mengatakan bahwa seorang aktivis adalah
131
orang yang mempunyai inisiatif dalam melakukan kegiatan dan mampu
mengorganisasi kegiatan, ia telah mencontohkannya. Banyak kegiatan di MCW
yang dinisiasi oleh LJK dan ia mencontohkan bagaimana mengorganisasi
kegiatan-kegiatan tersebut—karena anggota badan pekerja belum mempunyai
pengalaman itu. Ketika ia mengatakan bahwa seorang aktivis tidak boleh
menjadkan uang sebagai tujuan, ia sering menceritakan pengalamannya menolak
tawaran uang dari objek pantau dan menceritakan bahwa pilihan hidupnya sebagai
aktivis adalah pilihan hidup yang membuktikan bahwa ia tidak sedang menjadikan
uang sebagai tujuan hidupnya, seperti muncul dalam kalimat, “Kalau saya mau
kaya ya gampang,”.
Jadi selama belum ada orang yang memiliki status, disposisi, dan
pengalaman lebih daripada LJK, tidak akan ada yang memiliki modal simbolik
sebesar LJK. Ini menjelaskan mengapa sekalipun Didit maupun Zia yang pernah
menjabat sebagai ketua, tidak pernah memiliki kredit simboik sebesar LJK.
132
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk memenuhi
tujuan penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan dan menganalisis budaya politik
MCW, dan (2) mendeskripsikan dan menganalisis proses reproduksi budaya
politik tersebut, didapatkan dua kesimpulan:
a. Budaya politik MCW adalah ‘politik nilai’, yaitu pemosisian dirinya
sebagai entitas civil society yang berhadap-hadapan dengan negara;
melakukan kegiatan politik untuk mengimbangi kebijakan negara
supaya warga negara tidak lagi berada dalam posisi yang lemah.
Semua ini didasari keyakinan bahwa demokrasi pasca-soeharto telah
‘dicuri’ oleh elit politik lokal dan aktivitas ‘merebut kembali’
merupakan tindakan yang bertujuan untuk kebajikan.
b. MCW melakukan reproduksi budaya politik melalui kerja pedagogis
(pedagogic work) implisit, dengan cara melibatkan relawan dalam
aktivitas dan melakukan perbincangan-perbincangan untuk
mengimposisikan budaya politik MCW. Kerja pedagogis ini sebagian
besar dilakukan oleh seorang aktor yang memiliki pedagogic authority
(PAu), yang mana MCW bergantung padanya. Kerja pedagogis itu
sendiri ternyata menimbulkan konsekuensi logis berupa reproduksi
133
sosial, yaitu fenomena di mana relawan yang habitus-nya tidak sesuai
dengan budaya MCW merasa tidak nyaman dan kemudian pergi.
Dengan demikian, Malang Corruption Watch, salah satu kelompok yang
memposisikan dirinya sebagai entitas civil society yang berhadapan dengan negara
dan masih bisa bertahan di dalam posisi itu sampai sekarang, tidak bisa
menghindari kenyataan sosiologis bahwa keberdaan mereka tergantung pada satu
aktor yang memiliki pedagogic authority dan bahwa terjadi reproduksi sosial
dalam diri mereka.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai
berikut:
a. Menurut Bourdieu, orang-orang yang memiliki habitus yang berbeda pasti
tereksklusi dari lingkungan sosial yang melakukan reproduksi budaya.
Namun, di lapangan penulis mengamati ada orang-orang yang tetap
bertahan sekalipun habitus-nya tidak sesuai. Perlu ada penelitian lebih
lanjut mengenai apa yang membuat orang-orang itu bertahan dan sejauh
mana habitus itu bisa disesuaikan.
b. Diharapkan pula ada penelitian lebih lanjut mengenai non-government
organization lainnya yang memposisikan dirinya berhadap-hadapan
dengan negara untuk melihat apakah logika reproduksi budaya Pierre
134
Bourdieu yang telah penulis temukan dalam diri MCW juga ditemukan
dalam organisasi-organisasi tersebut.
c. Bagi Malang Corruption Watch, temuan ini bisa menjadi sarana refleksi
gerakan mereka. Kekuatan simbolis yang besar yang dimiliki aktor dengan
PAu, yaitu LJK, bisa menjadi modal yang diperhitungkan untuk mengatur
sistem yang lebih berkesinambungan di MCW.
135
Daftar Pustaka
Atkinson, J., Scurrah, M., Ross, C., Lingan, J., Pizarro, R., & Hobbs, J. (2009). Globalizing Social Justice: The Role of Non-Goverment Organizations in Bringing about Social Change. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. California: Stanford University Press.
___________(1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
Budiardjo, M. (2004). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Erman, E. (2007). Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka. In H. S. Nordholt, G. v. Klinken, & I. Karang-Hoogenboom, Politik Lokal di Indonesia (pp. 225-266). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fahrojih, I. (2004). Partisipasi (LSM) di Era Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di MCW dan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi-Kolusi). Skripsi S1 Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang
Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. New Jersey: Princeton University Press.
Hidayat, S. (2007). Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. In H. S. Nordholt, G. v. Klinken, & I. Karang-Hoogenboom, Politik Lokal di Indonesia (pp. 267-203). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ivanaly. (2007). Peran LSM dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Masyarakat Demokratis (Studi di Malang Corruption Watch). Skripsi S1 Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang.
Jenkins, R. (1992). Pierre Bourdieu: Key Sociologist. London and New York: Routledge.
Klinken, G. v. (2007). Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
136
Kurniawan, Luthfi J., et al. (2008). Negara, Civil Society, dan Demokratisasi. Malang: In-TRANS Publishing.
Neuman, W. L. (2007). Basics of Social Research. Boston: Pearson Education Inc.
Prasetyo, et al, (2002). Islam dan Civil Society. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN
Ramage, D. E. (1995). Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and The Ideology of Tolerance. London: Routledge.
Rosyada, et al, (2003). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
Rush dan Althoff. (2004). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.
Spradley, J.P. (1979). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinchart, and Winston.
___________. (1980). Participant Observation. New York: Holt, Rinchart, and Winston.
Surbakti, R. (1995). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Zuhro, R. S., et al. (2009). Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi. Yogyakarta: Ombak.
______________. (2011). Model Demokrasi Lokal: Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Jakarta: PT THC Mandiri.
137
LAMPIRAN
Lampiran 1. Standard Operating Procedure (SOP) Malang Corruption
Watch
1. Perjalanan Dinas
Pengertian:
• Perjalanan dinas adalah perjalanan untuk mengerjakan tugas-tugas dinas yang dibiayai oleh Program, Sekretariat atau Lembaga lain.
• Komponen biaya perjalanan adalah transportasi pesawat/ laut (at cost), transportasi darat (at cost), biaya penginapan dan hotel (at cost), pembelian peralatan lapangan (at cost), perdiem dan biaya komunikasi lapangan (tergantung kegiatan)
• Pembiayaan perjalanan dalam wilayah Kota di Malang Raya dan sekitarnya masuk kategori transport lokal.
Ketentuan:
1. Setiap perjalanan dinas harus disosialisasikan terlebih dahulu dalam Rapat Rutin.
2. Kepala divisi (atau person in charge) harus mengajukan TOR perjalanan dinas yang dilampiri budget anggaran kepada Koordinator Badan Pekerja.
3. Jika dianggap perlu, koordinator badan pekerja akan menyiapkan waktu khusus untuk rapat internal presentasi TOR rencana perjalanan dinas.
4. Pengajuan uang untuk perjalanan dinas diajukan kepada Bagian Keuangan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Biaya perjalanan di Malang Raya dan sekitarnya mengacu kepada kelayakan biaya yang mungkin terjadi
6. Kepala divisi (atau person in charge) akan menerima uang tunai sejumlah budget anggaran yang telah disetujui.
7. Kepala divisi (atau person in charge) harus membuat laporan hasil perjalanan/kegiatan dan laporan pemakaian dana maksimal 3 hari untuk laporan narasi dan laporan keuangan
8. Setiap laporan pemakaian dana perjalanan dinas harus disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.
138
9. Setiap hasil laporan narasi final diserahkan kepada Divisi general affairs untuk diarsip sebagai dokumen milik MCW.
10. Kepala divisi (atau person in charge) secara otomatis tidak akan dilayani permohonan pengajuan perjalanan dinas berikutnya selama belum menyelesaikan kewajibannya pada point 8.
11. Budget untuk perjalanan dinas diluar Malang Raya disesuaikan dengan jarak tempuh dan keuangan MCW.
2. Tentang Perdiem
Pengertian:
Perdiem adalah biaya-biaya yang sifatnya untuk keperluan hidup yang meliputi: biaya konsumsi, sumbangan dan biaya biaya pribadi lainnya. (Disesuaikan dengan kondisi keuangan MCW).
Ketentuan:
1. Perdiem hanya berlaku untuk untuk Badan Pekerja yang bekerja.
2. Besarnya total biaya perdiem disesuaikan dengan jumlah hari actual dan kondisi keuangan MCW.
3. Tentang Biaya Komunikasi Dinas: Ketentuan:
1. Biaya komunikasi dinas melalui wartel diganti sesuai dengan kuitansi pendukung.
2. Biaya komunikasi (handphone) Badan Pekerja di dalam Kota di Malang Raya at cost diganti sesuai keperluan dinas.
3. Untuk mendapat penggantian biaya penggunaan handphone, Badan Pekerja menghubungi Bagian Keuangan dengan membawa bukti perincian biaya komunikasi
4. Handphone dinas MCW digunakan hanya untuk kepentingan dinas.
5. Penggunaan handphone dinas MCW harus atas persetujuan dari Koordinator BP dan keuangan MCW.
4. Waktu Kerja dan Aktivitas
Ketentuan :
1. Waktu kerja resmi adalah pukul 10.00 - 16.00 berlaku setiap hari Senin hingga Sabtu.
2. Setiap aktivitas dan ketidakhadiran Badan Pekerja harus dilaporkan kepada Koordinator untuk
139
dicatat dalam buku aktivitas harian para Badan Pekerja.
3. Ketidakhadiran Badan Pekerja harus dapat dijelaskan dan diterima dalam rapat rutin MCW.
4. Setiap aktivitas (pekerjaan lain) Badan Pekerja diluar pekerjaan resminya di MCW harus dilakukan atas persetujuan Koordinator Badan Pekerja. Sebaliknya, setiap aktifitas (pekerjaan lain) Koordinator Badan Pekerja diluar tugas resminya di MCW juga harus disetujui melalui rapat MCW yang dihadiri oleh Badan Pekerja.
5. Rapat-Rapat Internal
Pengertian:
1. Rencana dan aktivitas setiap Badan Pekerja dilaporkan dalam rapat rutin.
2. Jadwal rapat rutin mingguan adalah setiap hari Jumat yang wajib diikuti oleh setiap Badan Pekerja.
3. Perubahan waktu rapat rutin mingguan akan diberitahukan oleh Koordinator Badan Pekerja.
4. Notulensi rapat rutin dibuat oleh Divisi general affairs dan didistribusikan kepada setiap Badan Pekerja sehari setelah rapat rutin.
5. Rapat internal program diusulkan oleh Kepala Divisi dan berkoordinasi dengan kepala program dan Koordinator Badan Pekerja.
6. Cuti Badan Pekerja
Ketentuan:
1. Setiap Badan Pekerja berhak untuk mengambil cuti umum maksimal 16 hari kerja setahunnya.
2. Diluar cuti umum Badan Pekerja berhak mengambil cuti khusus yang meliputi cuti sakit, cuti kelahiran, dan cuti urusan keluarga.
3. Pengambilan cuti umum oleh Badan Pekerja harus berdasarkan persetujuan kepala program dan koordinator BP MCW
4. MCW akan memberikan sumbangan dukacita atas meninggalnya keluarga langsung dan sumbangan pernikahan Badan Pekerja yang besarannya disesuaikan dengan anggaran lembaga.
5. Sebelum Badan Pekerja mengambil cuti harus disampaikan terlebih dahulu kepada kepala program dan koordinator BP untuk dibawa dalam rapat rutin. Kalau disetujui maka Koordinator BP akan menunjuk adinterim.
140
7. Fasilitas Kesehatan untuk Badan Pekerja
Ketentuan:
1. MCW memberikan fasilitas kesehatan untuk Badan Pekerja yang disesuaikan dengan kemampuan finansial MCW.
2. Bantuan kesehatan yang dapat diberikan kepada Badan Pekerja disesuaikan dengan keuangan MCW.
8. Masa Kerja Badan Pekerja
Ketentuan:
1. Badan Pekerja MCW adalah personil yang diangkat oleh forum rapat pleno melalui sebuah surat keputusan yang disahkan oleh Koordinator Badan Pekerja.
2. Masa kerja otomatis berakhir pada waktu yang telah ditetapkan sesuai surat keputusan atau ada keputusan lain, perpanjangan masa kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mandat dari Rapat Pleno MCW.
3. Setiap perekrutan tenaga konsultan dan volunteer oleh Kepala Divisi harus melalui persetujuan dari Koordinator Badan Pekerja MCW.
4. Setiap Kepala divisi yang memerlukan bantuan tenaga konsultan atau voluunter diwajibkan menyiapkan draft hak dan kewajiban/tugas sesuai dengan panduan yang ada.
9. Akhir Masa Kerja
Ketentuan:
1. Masa kerja Badan Pekerja berakhir jika masa pengabdiannya habis, diberhentikan atau berhenti atas kehendak sendiri.
2. Perpanjangan masa kerja dilakukan dengan kesepakatan kerja baru.
3. Pemberhentian secara tidak hormat dilakukan setelah Badan Pekerja yang bersangkutan mendapat surat peringatan.
4. Referensi kerja dapat diberikan oleh MCW sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
10. Keadministrasian dan surat-menyurat
Ketentuan:
1. Setiap surat keluar (surat dan fax messages) harus dibuat dengan mengikuti bentuk baku (Lihat Lampiran tentang Format Surat dan Fax) dan mengikuti petunjuk penomoran yang telah ditentukan.
141
2. Untuk kegiatan pengarsipan, semua surat keluar (diluar fax messages) harus dibuat dalam rangkap dua.
3. Setiap pengiriman paket dan surat-surat penting yang menggunakan jasa kurir harus mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan.
4. Setiap surat masuk (surat dan fax) akan dibubuhi tanggal penerimaan, distribusi kopi surat akan dilakukan kepada Badan Pekerja oleh Divisi general affairs.
5. Setiap kiriman paket bacaan (bulletin, majalah dan sejenisnya) akan dibubuhi tanggal penerimaan dan akan didisplay paling lama 1 minggu dari tanggal penerimaan.
6. Pengiriman surat-menyurat, pencatatan nomor surat masuk/keluar, pembubuhan tanggal penerimaan dan pengarsipan surat masuk/keluar/paket kiriman dilakukan oleh Divisi general affairs.
11. Pembelian Peralatan
Ketentuan:
1. Permohonan pembelian peralatan diajukan oleh Divisi general affairs /person in charge kepada Bagian Keuangan (lihat lampiran tentang form permohonan dana).
2. Semua pembelian peralatan harus disetujui oleh Koordinator Badan Pekerja MCW.
3. Setiap pembelian peralatan dilakukan oleh Divisi general affairs atau yang ditunjuk.
4. Setiap peralatan milik MCW diinventarisir oleh Divisi general affairs.
12. Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan
Ketentuan:
1. Setiap Badan Pekerja wajib menjaga dan menghindari kerusakan peralatan milik MCW.
2. Divisi general affairs akan menentukan teknisi untuk memelihara dan memperbaiki peralatan milik MCW.
3. Semua biaya pemeliharaan, perawatan dan penambahan (upgrade) peralatan milik MCW harus dimintakan persetujuan dari Bagian Keuangan.
4. Di luar peralatan kantor, semua peralatan milik MCW disimpan di Ruang dan Gudang .
5. Asuransi terhadap peralatan MCW dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan faktor resiko.
6. Cacat, kerusakan dan kehilangan peralatan milik MCW harus dilaporkan oleh pengguna kepada Divisi general affairs.
142
13. Penggunaan Peralatan Kantor
Ketentuan:
1. Setiap penggunaan telepon dinas/pribadi harus dicatat dalam buku yang sudah disediakan, dengan berpatokan pada prinsip efisiensi percakapan.
2. Penggunaan komputer pada jam kantor diprioritaskan untuk pekerjaan MCW .
3. Setiap pengguna harus mengecek koneksi ke saluran e-mail (disconect) setelah selesai melakukan e-mail dan down-load.
4. Penggunaan peralatan kantor (komputer, laptop, LCD, Handycame, telepon, fax, e-mail, printer dan atk, dll) oleh non Badan Pekerja harus dengan seizin Badan Pekerja.
14. Peminjaman dan Penghibahan Peralatan/ Buku
Ketentuan:
1. Penggunaan peralatan MCW diprioritaskan untuk keperluan program-program MCW.
2. Setiap peralatan dan buku milik MCW yang dipinjam harus diketahui dan seizin dari Divisi general affairs atau Badan Pekerja ditunjuk.
3. Setiap peralatan yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan tanggal perjanjian. Pelanggaran terhadap aturan ini harus dapat dijelaskan secara tuntas oleh peminjam.
4. Setiap peralatan dan buku yang dipinjam/dipakai harus dicatat dalam nota peminjaman alat (lihat lampiran tentang form peminjaman barang).
5. Untuk keperluan equipment history internal, setiap barang yang dipinjam harus dicatat dalam Log Book.
6. Peralatan MCW yang dapat dikeluarkan oleh Divisi general affairs atau person in charge.
7. Setiap peralatan yang dipinjam harus dicheck keutuhannya pada saat dikembalikan.
8. Daftar peralatan yang tidak dapat dipinjamkan (ke luar kantor):
PERALATAN
Komputer Komputer
Laptop
Printer
143
Audio visual Kamera
Tape recorder
handycame
LCD Projector
*) catatan : dapat keluar jika ada person in charge dari MCW
9. Setiap peminjaman alat oleh non Badan Pekerja harus disertakan dengan surat permohonan peminjaman alat yang ditujukan kepada Divisi general affairs.
10. Peminjaman alat dapat dilakukan dengan mekanisme memberi kontribusi pada MCW.
11. Kerusakan dan kehilangan peralatan MCW diatur dalam kesepakatan pinjam-pakai alat.
15. Pengarsipan dan database
Ketentuan:
1. Semua dokumen-dokumen penting manajemen (surat masuk/keluar, buku-buku, literatur, TOR serta laporan perjalanan) dan semua hasil dokumentasi audiovisual (film, slide, foto cetak, cassete rekaman dan sejenisnya) akan diarsipkan oleh Divisi general affairs dan Divisi inormasi, Dokumentasi dan Publikasi.
2. Penyimpanan dokumen-dokumen penting manajemen dilakukan di loker atau tempat lain yang disediakan.
3. Penyimpanan hasil dokumentasi audiovisual dilakukan di Ruang Arsip dan Gudang.
4. Semua pengarsipan akan dilakukan dengan standar database.
16. Transportasi Pengurus
Ketentuan
1. Transportasi yang diberikan esaran jumlahnya disesuaikan dengan kondisi/kemampuan lembaga.
2. Jika terdapat perubahan akan diberitahukan oleh Bagian Keuangan MCW dalam sebuah surat pemberitahuan resmi.
3. Jika kondisi keuangan memungkinkan maka pemberian tambahan biaya transportasi untuk hari raya dapat dilakukan.
144
17. Proposal Program
Pengertian:
Proposal program adalah sebuah rencana kerja Eksekutif MCW yang merupakan mandat Rapat kerja MCW, harus dikerjakan dalam periode waktu tertentu oleh Manajemen MCW, dan merupakan flagship MCW.
Ketentuan:
1. Penanggung jawab dari proposal program adalah Koordinator Badan Pekerja MCW.
2. Proposal program dibuat oleh Kepala Divisi bersama dengan timnya
3. Rencana pembuatan proposal program telah disosialisasikan dan didiskusikan dalam Rapat Rutin MCW/ Rapat Internal Program.
4. Setiap proposal program yang dimintakan dana kepada pihak lain harus diketahui dan disetujui oleh Koordinator Badan Pekerja.
5. Pembuatan anggaran proposal menggunakan format pembiayaan yang baku
18. Hubungan Kerja Jaringan
Pengertian:
Jaringan MCW adalah lembaga yang bekerja sama baik secara resmi maupun tidak resmi, dapat diawali dengan program bersama dan memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan visi dan misi MCW.
Ketentuan:
1. Pendahuluan pemilihan calon mitra (jaringan) dilakukan lewat sebuah proses assessment tentang record lembaga maupun personal Badan Pekerja.
2. Hasil assessment didiskusikan dalam rapat rutin MCW/ rapat internal program.
3. Jika diperlukan, MCW akan melakukan capacity building berbentuk pelatihan (inhouse training) kepada jaringannya.
19. Acara atau pengadaan kegiatan yang diorganisir oleh MCW
145
Ketentuan
1. Penanggung jawab acara/kegiatan adalah kepala divisi yang bersangkutan.
2. Kepala divisi menyiapkan TOR dan budget anggaran.
3. Ketua Panitia berasal dari Badan Pekerja/non Badan Pekerja yang ditunjuk oleh kepala divisi.
4. Ketua Panitia bertanggung jawab atas pengajuan uang muka (minimal 6 hari sebelum acara/kegiatan) dan pelaporan penggunaan dana kepada Bagian Keuangan MCW.
5. Ketua Panitia akan menerimada dana tunai sesuai dengan budget yang disetujui.
6. Ketua panitia membuat laporan narasi dan keuangan setelah selesai acara/kegiatan maximal 3 hari setelah selesai acara/kegiatan.
6. Kepala divisi bertanggung jawab terhadap laporan yang dihasilkan dari acara/kegiatan.
20. Penerbitan dan Publikasi MCW
Ketentuan
1. Materi penerbitan dan publikasi bersifat mengkampanyekan ide-ide dan program kerja MCW.
2. Penyiapan materi dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan telah ditetapkan.
3. Setiap publikasi dan penerbitan MCW harus mencantumkan secara lengkap informasi tentang MCW.
4. Final draft penerbitan dan publikasi MCW harus direview oleh Koordinator Badan Pekerja.
5. Distribusi penerbitan dan publikasi MCW dilakukan oleh Divisi general affairs.
21. Keamanan
Ketentuan
1. Badan Pekerja juga bertugas setiap harinya dari pukul 19.00 wib hingga 06.00 wib.
2. Setiap sore hari dilakukan pengecekan terhadap komputer (shut down), kabel-kabel listrik, penutupan jendela, kunci pintu (hanya pintu utama yang masih terbuka) kantor.
3. Pintu belakang hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak saja.
4. Jika sedang tidak digunakan, Ruang kerja, Ruang Arsip dan Gudang harus selalu dikunci pada saat diluar jam kantor.
5. Kunci ruang kerja, ruang Ruang Arsip dan Gudang dimiliki oleh Koordinator Badan Pekerja, dan Kepala Divisi/Bagian.
146
22. Kebersihan dan Penerimaan Tamu
Ketentuan
1. Setiap pagi hari dilakukan pembersihan kantor MCW oleh Badan Pekerja kebersihan setiap pagi hari kerja.
2. kebersihan meliputi ruang kerja, ruang rapat/tamu, ruang dapur, ruang TV dan ruang tidur, paling lambat pukul 09.30 WIB sudah selesai semua.
3. Setelah selesai dipakai gelas/cangkir, piring, kasur lipat, bantal, koran, majalah dan sejenisnya harus dikembalikan ke tempatnya semula dalam kondisi baik dan bersih.
4. Merokok diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kaidah kebersihan.
5. Untuk menerima tamu Bagian Administrasi da Kesekretariatan yang mengkonsolidasikannya.
23. Peserta Magang dan Tempat Riset
Ketentuan
1. Peserta Magang dan Peneliti akan didampingi oleh Badan Pekerja yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan dari Koordinator Badan Pekerja.
2. Peserta Magang wajib mengikuti seluruh peraturan yang ada di MCW, termasuk jam kerja. 3. Peserta magang dan peneliti wajib memberikan 1 (satu) kopian laporan kepada MCW. 4. Penggunaan data dan informasi bagi peserta magang dan peneliti hanya pada kepala divisi
indok dan publikasi atau koordinator BP atau orang yang ditunjuk oleh koordinator BP MCW.
24. Permintaan Menjadi Pembicara
1. Pada prinsipnya MCW sangat terbuka kepada siapa saja yang meminta menjadi pembicara dalam kegiatan public/masyarakat, baik lembaga maupun komunitas/jaringan.
2. Khusus permintaan menjadi Pembicara kepada MCW, yang diajukan oleh penyelenggara kekuasaan akan dibahas dalam Rapat Mingguan.
3. Koordinator atas prakarsa sendiri atau usulan dari anggota Badan Pekerja dapat mengagendakan rapat khusus untuk membahas permintaan pembicara kepada MCW apabila permintaan tersebut perlu segera ditindaklanjuti. Pemberian tugas sebagai Pembicara disesuaiakan dengan kapasitas pribadi atau job description divisi.
4. Apabila ada honor sebagai pembicara yang jumlahnya Rp. 100.000 atau lebih maka akan dibagi 50% untuk pembicara yang bersangkutan dan 50% untuk MCW.
5. Apabila yang mengundang adalah penyelenggara Negara (ekskutif, legislatif, yudikati), maka pemberian honornya harus dipertimbangkan, apakah sebagai biaya transportasi kegiatan (pengganti tiket, dan semacamnya) atau sebagai uang kompensasi kepentingan. Kalau sebagai uang kompensasi maka harus ditolak.
147
Lampiran 2. Foto-Foto
Suasana Rapat Insidentil MCW di gazebo. Tampak penulis sedangterlibat dalam rapat itu (duduk kedua dari kanan). Yang berbaju hijauadalah Zia Ulhaq, yang pada saat itu masih menjabat sebagaiKoordinator MCW
Luthi J. Kurniawan sedang memberikan arahan
Seorang relawan sedang melakukan input data ke komputer.
148
Suasana rapat rutin di meeting room (ruang pertemuan) MCW. Saat itu Didit, yang masih menjabat sebagai Wakil Koordinator MCW, sedang memimpin rapat. Tampak penulis terlibat dalam rapat (duduk pertama dari kiri)
Aksi demonstrasi bersama pedagang Pasar Tradisional di depan Balaikota Malang Tanggal 25 November 2010
149
Suasana Focus Group Discussion Riset Bisnis-Politik Tembakau Tanggal 18 Januari 2011.
Suasana Diskusi Publik “Membangun Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel, tanggal 30 November 2010 di Malang.
Lampiran
MCW ARabu, 18 MeMALANG – Malang CorupTerutama tingdisampaikan MCW menginyang member’’Soal transpaSelain itu karMCW, M DidSedangkan sokepala sekolakepala sekolaMCW juga mdihentikan saKetua Komisyang dipimpinmelakukan peCara lain untuDalam waktuitu diserahkanDalam pembakerja anggaradipanggil KomKepala sekola4 dan SMANSelanjutnya ksebelumnya. Karena itu diatahun lalu seb‘’Kami sangamemberatkanSalah satu conwisuda dan re Sumber: M
Gedung P
Wednesda
MALANGdianggap manggaran. Kritik tersmerupakansetelah Jemseharusnyberbintang”Tidak ad
n 3. Artikel
Adukanei 2011 15:28 Keluhan soal bption Watch (Mgginya biaya pesaat hearing di ngatkan agar peratkan dan paraaransi, pada tahrena biayanya ydit Soleh. oal inkonsistensah. ’’Contohnyaahnya berganti, meminta agar se
at ini juga. Kari D DPRD Kotannya. Politisi Pemantauan di seuk menekan tin
u tak lama lagi, nn ke Dinas Pendahasan perwali an sekolah. Bahmisi D untuk diah yang dipang
N 8. kata Christea, pi
a mengingatkanbesar Rp 7,5 jutat konsen pada pn wali murid,’’ kntohnya telah mekreasi pada tah
Malang Post
Pemkab Meg
ay, 18 May 2
G– Gedung kmelanggar n
sebut dilontarn daerah denmber. Koord
ya anggaran ug tersebut, di
da korelasi po
l Berita Me
Biaya P
biaya pendidikanMCW) dan Foruendidikan dan bgedung DPRD
enerimaan siswa kepala sekolahhun lalu, ada salyang mahal, ada
si, Didit menguna, ketika pesertapeserta didik kmua jenis pung
rena itu MCW ma Malang, ChriPartai Demokraekolah.
ngginya biaya penaskah perwalididikan. tentang SBPP,
hkan kemarin seimintai penjelas
ggil komisi yang
ihaknya juga m
n, kemungkinanta bakal dipertapendidikan. Kakata dia.
mendesak menghun depan. (van
t (cetak/diun
gah Dinilai
2011
kantor Pemkanilai kepantas
rkan Malangngan jumlah dinator Badanuntuk pembaipakai untuk ositif antara g
edia Menge
Pendidik
n, memang kemum Masyarakat buruknya pelaya
Kota Malang, wa baru pada tahh yang kerap inklah satu sekolaha masyarakat ya
ngkapkan ada sa didik sudah di
kemudian harusgutan liar saat pmeminta Komisstea Frisdiantar
at ini mengajak
endidikan, katai tentang SBPP
lanjut dia, telahejumlah kepala san. g membidangi p
meminta sekolah
n pungutan SBPahankan untuk tarena itu kami b
ghapus biaya pen/avi)
nduh dari v
Tak Pantas
ab Malang ysan karena te
g Corruption warga miskin Pekerja MC
angunan gedumengentas k
gedung mega
enai MCW
kan
mbali muncul bePeduli Pendidi
anan pendidikankemarin siang h
hun ini berlangskonsistensi. Koh yang tidak traang tidak bisa m
sebuah kebijakainyatakan gratiss bayar,’’ ungkaenerima siswa bsi D untuk memra mengatakan, MCW dan berb
a Christea, pihakyang menjadi a
h diteliti secara sekolah yang re
pendidikan ini,
h untuk tidak m
PP tahun ini tidaidak naik.
berusaha semaks
endaftaran siswa
versi online)
ang sedang derlalu megah
Watch (MCin (gakin) terCW,M Diditung yang dibkemiskinan wah yang men
ersamaan dengaikan mengadukan ke Komisi D hingga sore harsung transaparaondisi ini terjadiansparan dalam menjangkau,’’ b
an yang tidak kos dalam biaya papnya. baru dan setelah
mantau di sekolapersoalan ini m
bagai elemen m
knya sedang meacuan pungutan
detail tentang uencana kerja an
yakni kepala S
mengalokasikan
ak mengalami p
simal mungkin
a baru dan regis
)
dibangun di Kdan mengha
W) karena Krbesar kedua t Sholeh, menbuat mewah hwarga Kabupnelan anggara
an tahun ajaranan berbagai perDPRD Kota M
ri. an, wali murid tii pada tahun lalmengumumkan
beber Koordinat
onsisten ketika pendidikan, aka
h penerimaan sah-sekolah. menjadi perhatiamasyarakat untu
embahas perwan biaya pendidik
usulan anggarannggaran sekolah
SMKN 6 dan 4
lagi pos anggar
peningkatan. Ba
agar biaya pen
strasi serta men
Kota Kepanjambur-hambu
Kabupaten Mdi Jawa Tim
ngatakan, hingga mirippaten Malangan besar deng
150
n baru. Kemarinrsoalan pendidik
Malang. Pengadu
idak dikenai bialu. n hasil ujian mtor Badan Peker
terjadi pergantan tetapi ketika
siswa baru haru
an serius komisuk bersama-sam
ali tentang SBPPkan bagi murid
n untuk rencanahnnya tidak dije
4, SMAN 3, SM
ran yang sudah
ahan SBPP tert
ndidikan tidak
niadakan anggar
jen, urkan
Malang mur
p hotel g. gan
n, kan. uan
aya
masuk. rja
tian
s
si ma
P. baru
a elas
MAN
ada
tinggi
ran
151
kinerja pemerintahan. Harusnya, alokasi pendidikan dan mengentaskan warga miskin yang lebih diprioritaskan daripada gedung megah itu.Tidak pantas lah gedung megah itu dibangun,” ujar Didit kepada harian SINDO,kemarin. Dijelaskan, ada nilai kepantasan yang dilanggar Pemkab Malang dalam pembangunan gedung tersebut. Sebab masih banyak warga miskin yang membutuhkanulurantanganPemkab Malang. Pertolongan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan APBD sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan APBD untuk pembangunan gedung mewah,katanya,secara tidak langsung Pemkab mengabaikan fakta kemiskinan sebenarnya. Bahkan, MCW menyatakan bahwa telah terjadi penghambur-hamburan uang rakyat untuk sesuatu yang sebenarnya tidaksangatpentingdan mendesak. Bahkan, Didit menduga pembangunan gedung megah dengan anggaran yang hingga saat ini sudah menelan Rp7,5 miliar tersebut hanyalah untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu saja. ”Kita menolak pembangunan gedung Pemkab dengan anggaran besar itu.Dan kita meminta agar Pemkab Malang mengkaji lagi pembangunanyangmenelananggaran besar ini,”ungkapnya. Sekadar diketahui, gedung Pemkab Malang yang digarap PT Anugrah Citra Abadi ini, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Malang selama beberapa tahun (multy years), sejak 2008 lalu. Hingga saat ini pembangunannya baru sekitar 75%. Rencananya, gedung yang akan dijadikan sebagai pusat pelayanan Pemkab Malang tersebut baru akan dipakai pada 2013 mendatang. Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna saat dihubungi harian SINDO melalui ponselnya, mengatakan,MCW salah dalam menilai pembangunan gedung baru Pemkab Malang tersebut.Dia mengelak dikatakan pembangunan gedung Pemkab tersebut sebagai langkah yang tidak pantas.Rendra beralasan, 10 tahun lalu saja, sebelum Kabupaten Malang membangun gedung,Pemkab Ponorogo sudah membangun gedung yang kemewahannya melebihi bangunan milik Pemkab Malang yang ada saat ini. ”Perlu diketahui, harga tanah di Kota Kepanjen saat ini sangat mahal makanya agar tidak menelan biaya besar, kita bikin gedung kantor Pemkab Malang setinggi mungkin. Makanya terlihat megah,”tuturnya. Sebab jika tidak dibangun bertingkat,biaya untuk pembebasanlahansertaanggaranyang diperlukan lebih banyak lagi. Apalagi, katanya, gedung ini merupakan pusat Pemkab Malang. zia ulhaq_Semua pegawai dan dinas akan berkantor di gedung ini sehingga harus dibangun besar. Terkait status Kabupaten Malang yang jumlah warga miskinnya terbanyak kedua di Jatim, kata Rendra, hal itu tidak bisa dijadikan patokan.Alasannya, jumlah penduduk Kabupaten Malang memang lebih besar daripada daerah lain.Sehingga, otomatis jumlah warga miskin juga lebih banyak.Saat ini,jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 2,7 juta orang. Sumber: Seputar Indonesia (online)
\
152
MCW Protes Pelayanan Publik di Malang Raya Penulis : Bagus Suryo Rabu, 13 April 2011 15:07 WIB
Komentar: 0 0 0
MI/Bagus Suryo/wt
MALANG--MICOM: Malang Corruption Watch (MCW), Kota Malang, Jawa Timur, berunjuk rasa memrotes buruknya pelayanan publik di pemerintah daerah Malang Raya meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Aksi tersebut dilakukan sekitar 30 orang di Alun-Alun Malang, Rabu (13/4), dengan berorasi mengecam pemerintah daerah itu karena pelayanan publik yang diberikan sangat buruk. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster. "Padahal sudah ada Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi mengapa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih mengecewakan," kata Koordinator Badan Pekerja MCW Muhammad Didit Soleh kepada wartawan disela-sela unjuk rasa. Ia menjelaskan, buruknya pelayanan publik diketahui setelah MCW melakukan survei selama Februari lalu terkait hal itu. Sehingga semua data yang dimiliki berdasarkan hasil penelitian, dan bukannya asal bicara. Itu sebabnya, ujar Didit, MCW getol menyuarakan perbaikan pelayanan publik, sebab sebanyak 66% dari 1.000 orang responden yang diwawancarai menyatakan pelayanan
153
yang diberikan tidak memuaskan. Buruknya pelayanan publik antara lain terjadi pada Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, kecamatan, dan desa/kelurahan. Sebagian besar masyarakat menyatakan dalam pengurusan dokumen petugas tidak ramah dan masih adanya pungutan di luar ketentuan. (BN/OL-01) Sumber: Media-Indonesia (online)
MCW Desak Dewan Awasi Pengelolaan Dana ZIS
Kamis, 14 Juli 2011 20:36:24 WIB Reporter : Yatimul Ainun
Malang (beritajatim.com) - Malang Corupption Watch (MCW), mendesak DPRD Kota Malang, segera membentuk tim untuk mengawasi pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS), yang dikelola Pemerintah Kota Malang. Tim tersebut untuk memastikan pertanggungjawaban dana yang dipungut dari pegawai dilingkungan Pemkot Malang. "Dana tersebut ditaksir yang terkumpul dari ZIS itu bisa mencapai Rp 910 juta per bulan atau mencapai Rp 19.920 miliar per tahun," kata Koordinator Badan Pekerja Malang Corupption Watch (MCW), Didit Soleh, Kamis (14/07/2011). Asumsinya beber Didit, terdapat sekitar 13 ribu pegawai dilingkungan pemkot dan setiap pegawai dipotong gajinya 2,5 persen tiap bulan. "Dewan harus memaksimalkan fungsi pengawasannya dengan meminta transparansi kepada pemkot siapa yang mengelola ZIS itu," pintanya ditemui di kantor dewan. Didit kawatir dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu atau kepentingan kelompok. "Dan yang patut diawasi oleh legislatif adalah bagaimana pengelolaan dananya, mekanisme pendistribusiannya sehingga tepat sasaran dan transparansi dana yang terkumpul," jelasnya. Apalagi aku Didit, Kota Malang dua tahun kedepan melangsungkan pemilihan kepala daerah. "Kami kawatir digunakan untuk kepentingan tertentu dan masyarakat tidak tahu kalau itu dana dari ZIS pegawai," katanya. Sebelumnya, Walikota Malang menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota tentang himbauan pemotongan gaji PNS dilingkungan Pemkot Malang untuk ZIS. SE ini sendiri dianggap MCW menyalahi UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Didit menambahkan, seharusnya pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat bentukan pemerintah atau pemerintah daerah atas usulan Kementerian Agama. Pemerintah hanya sebatas membantu saja. "Namun, dalam kasus di Kota Malang ini, Pemkot mengambil alih peran badan amil. Mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Ini sudah melampaui batas, jelas menyalahi aturan yang ada," tegas Didit. Menanggapi apa yang diminta MCW, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiadji menegaskan siap untuk memanggil SKPD terkait untuk meminta paparan tentang ZIS ini. "Kami ingin tahu seperti apa keinginan pemkot," akunya. Menurut Sutiadji, dalam struktur lembaga ZIS ini harus dikelola oleh orang yang paham hukum dan profesional. Pemkot tidak boleh terlibat di dalamnya. "Untuk memungut ZIS dari pegawai juga harus disertai dengan Surat Keputusan Walikota Malang sebagai payung hukumnya. Tanpa SK Walikota, dilarang untuk melakukan pemungutan," tegasnya.
Secara terpissaat ini belummenyalahi at
Sumber: w
MCW PMonday, 04 Ju
User Rating:
Poor
Pengu
MALANG- kecewa ataterhadap inmelayangk
Menurut ke23 Mei 201tentang pejkemudian o"Sayangnykami kira k
Dalam pendikecualika
sah, Kepala Bagm direalisasikanturan," katanya
www.beritaj
Protes Suly 2011 20:42 A
/ 0
urus MCW me
Organisasi pas sikap Pemnformasi penkan surat lagi
epala divisi in1 lalu pihaknjabaran APBoleh pemkot
ya, surat balaurang tepat d
olakan itu, Man untuk diko
gian Kesejahten program ZIS a.[ain/ted]
jatim.com (
SuratnyaNAS
Best Rat
mpertanyakan
pengawas prmerintah Kotanjabaran APBi karena pen
nformasi, doknya meminta
BD. Namun smelalui Dina
asan itu berisdan tidak se
MCW mendaonsumsi oleh
raan Rakyat Petersebut. "Mas
online)
a Ditolak
te
n surat merek
raktek korupa (Pemkot) MBD tahun 201olakan itu di
kumentasi, da permohonasurat MCW bas Komunikasi tentang pesuai peratura
pat penjelash publik. Nam
emkot Malang,sih menunggu
k Pemko
ka di Pemkot M
psi, Malang CMalang meno11.Karena itunilai tidak tep
dan publikasian informasi taru mendap
asi dan Informnolakan atasan,"jelas Ruc
an pemkot bmun setelah m
Edi Sulistyo mpayung hukum
ot
Malang. (anas-
Corruption Wolak permintau kemarin (4pat.
MCW, Ruchterkait surat atkan balasamasi (Dinkoms permohonachul.
bahwa ada inmelakukan k
menyatakan hinmnya agar tidak
-malangnews)
Watch (MCW) aan mereka /7/2011), MC
hul Jannah, pkeputusan (S
an 30 hari minfo). an MCW yan
nformasi yangkonfirmasi, M
154
ngga k
)
CW
pada SK)
ng
g MCW
155
mengetahui bahwa sesuai undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008, pasal 17 bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan untuk diterima publik.
Atas dasar itulah dinas kominfo yang bertindak sebagai PPID dinilai tidak mematuhi UU dan peraturan yang berlaku. Karena tidak melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta dan tidak menyertakan hasil uji konsekuensi dalam surat yang diterima MCW.
Dalam kenyataannya, SK penjabaran APBD 2011 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Karena dokumen itu seharusnya bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. “Dengan bukti itu maka PPID Kota Malang telah menutup akses informasi kepada publik,”jelas Wakil Kordinator MCW, Gadi Makitan. Ia menambahkan bahwa dari9 SK penjabaran APBD 2011 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dikonsumsi publoik.
Berdadarkan bukti di atas, maka MCW menyatakan keberatan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi nomor 1. Tahun 2010 pasal 30 ayat 1 huruf D. Karena itu MCW tetap meminta dokumen SK Penjabaran APBD 2011 sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Jika keberatan ini tidak ditanggapi, maka MCW mengancam akan membawa kasus ini ke Komisi Informasi Daerah (KID) di Surabaya.
Adapun Humas Pemkot Malang mengaku telah menerima surat keberatan dari MCW. Namun humas mengaku bahwa surat MCW tidak memiliki spisifikasi tentang kasus yang ditanyakan. “ Kalau yang ditanyakan secara global, MCW bisa menanyakan langsung pada DPRD. Karena penjelasan terinci ada di sana. Sedangkan pemkot bertugas sebagai pelaksanan saja,”kilah Kahumas Pemkot Malang, Budi Herwanto.**
Sumber: www.malangnews.com (online)
Belasan Wali Murid Mengadu ke DPRD Malang 27 Jun 2011 16:20:04| Pendidikan/Pesantren | Dibaca 135 kali | Penulis : Abdul Malik
156
Malang - Sedikitnya 19 wali murid di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengadu ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat memprotes penarikan iuran pada pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Para wali murid itu didampingi oleh LSM Malang Corruption Watch (MCW), Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Malang (KMPP), Kelompok Mahasiswa Peduli Pendidikan serta Lembaga Bantuan Hukum Malang. Wakil Koordinator MCW, Gadi Makitan mengatakan, tujuan pengaduan untuk menindaklanjuti laporan 19 wali murid yang mengaku telah dimintai uang oleh pihak sekolah pada pelaksanaan PSB. "Dalam pengaduan ini, kami meminta DPRD menindaklanjuti adanya penarikan yang diluar ketentuan itu, sehingga wali murid tidak dirugikan dengan adanya pungutan di luar ketentuan tersebut," katanya. Gadi menjelaskan, penarikan iuran pada pelaksanaan PSB telah menyalahi aturan perundang-udangan dan konstitusi negara, seperti yang termuat dalam pasal 28C ayat 1 UUD 45, yang berbunyi "setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Selain itu, dipertegas pula oleh UUD 45 Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 12 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk menjadi orang beriman, dan sejahtera sesuai HAM". "Berdasarkan kedua landasan konstitusi negara itu, jelas penarikan iuran pada pelaksanaan PSB merupakan pelanggaran," katanya. Sementara hasil monitoring MCW sejak tahun 2008 hingga 2011, jenis penarikan iuran di sejumlah sekolah wilayah Kota Malang tersebut meliputi uang pendaftaran masuk sekolah, uang SPP/komite, uang OSIS, uang study tour, uang wisuda, uang paguyuban serta sejumlah penarikan lainnya. "Ada wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya di SD wilayah Joyogrand
157
Malang, dan mengaku diwajibkan membayar Rp600 ribu, padahal ketentuan ini di sekolah lain tidak ada," katanya. Menanggapi aduan itu, Ketua Komisi D DPRD Malang, Dr Chiristea Fridiantara mengaku akan meminta bukti dari wali murid terkait adanya penarikan tersebut. Selain itu, DPRD Malang akan segera memanggil kepala dinas pendidikan setempat untuk menjelaskan adanya penarikan iuran tersebut. "Kami meminta agar wali murid bisa menindaklanjuti masalah ini dengan positif, yakni meminta bukti dulu kepada sekolah, sehingga DPRD bisa melakukan testimoni," katanya.
Sumber: www.antarajatim.com (online)
MCW : Pemkot Tidak Transparan Terkait Proyek Block Office
BATU – Ada kesan Pemkot Batu tertutupnya dalam memberikan informasi penggunaan anggaran untuk proyek block office. Salah satu indikasinya, tidak pernah ada laporan tentang proyek yang disampaikan ke DPRD. Baik itu detail kontrak kerjasama antara rekanan, detail anggaran hingga perkembangan proyek. Malang Corruption Watch (MCW), menyoroti kesan tertutupnya informasi tentang proyek. Pasalnya, dengan menggunakan anggaran dari APBD, masyarakat berhak tahu informasinya tentang perkembangan proyek hingga detail penggunaan anggaran. Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW, Gadi Makitan menyatakan, dengan tertutupnya informasi tentang proyek bernilai puluhan miliar itu, malah menimbulkan kecurigaan. ”Masyarakat berhak tahu mengenai penggunaan anggaran untuk pembangunan block office itu. DPRD Kota Batu sendiri seharusnya memaksimalkan fungsi pengawasan mereka, dan berhak mendapatkan data dari Pemkot Batu,” ujar Gadi, Kamis (19/5). Salah satu instrument yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi penggunaan anggaran dan berbagai informasi tentang proyek block office adalah dengan UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan perundangan ini, masyarakat berhak tahu anggaran menggunakan dari pos apa dan detail peruntukkannya. ”Dengan perundangan itu, seharusnya legislative juga berhak mendapatkan informasinya. Kalau tidak bisa mendapatkan informasi itu, patut dipertanyakan kinerja dewan. Bisa jadi dewan sendiri bermalas-malasan dalam memaksimalkan fungsi pengawasannya,” urai Gadi. MCW sendiri menurut Gadi, dalam waktu dekat akan melakukan kajian tersendiri tentang
158
proyek block office. Bahkan juga berniat untuk mengajukan permintaan informasi mengenai penggunaan anggaran itu. Beberapa saat lalu, DPRD Kota Batu sendiri mengeluhkan bila tidak pernah menerima laporan perkembangan proyek dari Dinas Cipta karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batu selaku leading sector proyek block office. Direncanakan pada Mei ini juga digelar hearing antara dewan dengan DCKTR mengenai proyek tersebut. Sementara dewan sendiri terkesan enggan membentuk tim khusus atau panitia khusus pengawasan proyek block office. “Tidak diperlukan tim khusus untuk pengawas proyek, karena sudah ada tim pengawas proyek dari dinas. Kecuali bila ketua dewan ingin membentuk tim khusus itu. Saat ini kami hanya ingin mengetahui perkembangan dari proyek itu dulu,” papar Agus Hariyanto, Ketua Komisi D DPRD Kota Batu beberapa saat lalu. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, Susetya Herawan tidak bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Tidak ada jawaban saat coba dihubungi di ponselnya.mal
Sumber: surabayapagi.com (online)