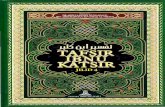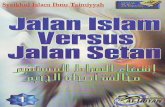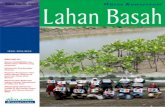RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM ...
RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUMPERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG
SAKSI DALAM TALAK
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh:
JOSHUA SUHERMANNIM. 11521104436
PROGRAM S1JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2019 M/ 1441 H
ABSTRAK
Joshua Suherman, (2019) : RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZMDENGAN HUKUM PERKAWINAN DIINDONESIA TENTANG SAKSI DALAMTALAK
Talak adalah sesuatu yang tidak dinginkan oleh semua orang, namunwujudnya talak pada hakikatnya adalah untuk menyelesaikan permasalah yangterjadi dalam rumah tangga. Agama mensyariatkan pernikahan untuk memenuhikemaslahatan hamba, baik dalam bidang duniawiyah maupun dalam bidangdiniyah, maka disyariatkannya talak adalah untuk menyempurnakan pernikahan,karena apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tentu harusdicarikan jalan keluarnya. Skripsi ini membahas seputar hukum persaksian dalamtalak, yang menjadi pokok permasalahannya adalah pendapat Ibnu H{azm yangmengatakan bahwa wajib menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak, yangmana hal ini adalah berbeda dengan apa yang telah menjadi ijmak dikalanganjumhur ulama fikih, kemudian ditemukan pula dalam hukum perkawinan diIndonesia bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang PengadilanAgama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah pendapatIbnu H{azm relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia tentang saksi dalamtalak.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya penelitian inidilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka (Library Research), yang dalampenelitian ini adalah kitab al-Muh}alla> karya Ibnu H{azm dan buku-buku yangmembahas tentang hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifatdeskriptif, yaitu mendeskripsikan pendapat Ibnu H{azm tentang saksi dalam talaksecara sistematis kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi padahukum perkawinan di Indonesia saat ini.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulanbahwa adanya kesamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu H{azm dan hukumperkawinan di Indonesia. Baik Ibnu H{azm maupun hukum perkawinan diIndonesia sama-sama mewajibkan adanya saksi pada saat ikrar talak, namunterdapat perbedaan yang lebih mendasar sehingga penulis menyimpulkan bahwapendapat Ibnu H{azm dengan hukum perkawinan di Indonesia tentang saksi dalamtalak tidak relevan dan tidak bisa dikatakan bahwa ketentuan perceraian diIndonesia harus di depan Sidang Pengadilan Agama adalah berdasarkan pendapatIbnu Hazm, karena terdapat perbedaan dalam hal teknis, yang mana hal ini dapatmenentukan sah atau tidaknya talak seseorang.
Kata Kunci: Ibnu Hazm, Saksi, Talak.
Motto
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran”
(QS. An-Nahl [16]: 90)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Almamaterku Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Saudara dan Saudariku
Keluargaku Ma’had al-Jami’ah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Dan Untuk masa depanku yang sukses dan bahagia
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusanbersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
1. KonsonanDaftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث S|a S| Es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح H}a H} Ha (dengan titik diatas)
خ Kha Kh Ka dan Ha
د Dal D De
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Es dan Ye
ص S}ad S} Es (dengan titik dibawah)
ض D}ad D} De (dengan titik dibawah)
ط T}a T} Te (dengan titik dibawah)
ظ Z}a Z} Zet (dengan titik dibawah)
ع ‘Ain ‘__ Apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qof Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah __’ Apostrof
ي Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiriatas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasinya sebagaiberikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا Fath}ah A A
ا Kasrah I I
ا D}ammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
يى Fath}ah dan Ya Ai A dan I
ىو Fath}ah dan Wau Au A dan U
Cantoh:
كيف : kaifa هول : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat danhuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Huruf dan harakat Nama Huruf dan tanda Nama
_ى\_ا Fath}ah dan alifatau ya a>
a dan garisdiatas
ىي Kasrah dan ya i>i dengan garis
diatas
ىو D}ammah dan ya u>u dengan garis
diatasContoh:
مات : ma>ta قيل : qi>la
رمى : rama> يموت : yamu>tu
4. Ta Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua yaitu ta marbu>t}ah yanghidup dan mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah tranlitersinyaadalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakatsukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata terakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,maka ta marbu>t}ah itu di transliterasikan dengan [h].
Contoh:
روضة األطفال : raud}ah al-at}fa>l
نة الفاضلة المديـ : al-madi>nah al-fa>d}ilah
الحكمة : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan sebuah tanda tasydi>d ( ◌), dalam transliterasi inidilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ربـنا : rabbana>
الحق : al-h}aqqu
نـعم : ni”ima
عدو : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului olehhuruf kasrah ى maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh :
علي : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عربي : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan denganhuruf ال (alif dan lam). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandangditransliterasi sesuai dengan bunyinya baik dikuti oleh huruf qamariyyahmaupun syamsyiyyah.
Contoh:
س م ش ل ا : asy-syamsu
ة ل ز ل ز ل ا : az-zalzalah
ة ف س ل ف ل ا : al-falsafah
د ال ب ل ا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanyaberlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bilahamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisanArab ia berupa alif.
Contoh:
ن و ر أم ت : ta’muru>na شيء : syai’un
النـوء : al-nau’ أمرت : umirtu
8. Huruf Kapital
Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentangpenggunaan huruf kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awalnama orang, tempat atau bulan dan huruf pertama pada permulaankalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Contoh:
Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l
Syahru ramad}a>n al-laz|i> unzila fi>hi al-Qur’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Al-gaza>li>
Al-Munqiz| min al-D{ala>l
9. Penulisan bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasaIndonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Seperti kataal-Qur’an, Sunah, khusus dan umum. Namun jika kata-kata tersebutmenjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasisecara utuh.
Contoh:
Fi Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
i
KATA PENGANTAR
، هو الذي خلق الموت والحيوة لنبلوكم أيكم ورنا لغفور شكرب ا الحزن إن ذي أذهب عن ال هللاد مالح
الللهم صل على سيدنا محمد، خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى اله وهو العزيز الغفور.،أحسن عمال
الطيبين، وأصحابه األخبار أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Puji dan syukur kepada Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la> yang telah
melimpahkan segala rahmat dan karunia -Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Sayyidul Mus}t}ofa baginda Rasulillah Muhammad S}allalla>hu
‘Alaihi wa Sallam. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir
nanti, A>mi>n.
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan
kaum muslimin pada umunya terutama pada diri penulis sendiri. Semoga dengan
tersusunya skripsi dengan judul “RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG SAKSI
DALAM TALAK” ini, tidak hanya sekedar menambah khazanah keilmuan,
namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan
hendaknya.
Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan
dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini
ii
penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Yasriman dan Ibunda tercinta
Yarnida yang telah merawat penulis dari kecil hingga sekarang dan telah
memberikan semua do’a dan kasih sayang dengan setulus hati yang tidak
akan pernah dapat penulis balas sampai kapanpun dan seluruh keluarga
besar penulis, Ambo, Ayek, Mak Uwo, Mak Aciak, Uda-Uda, Uni-Uni dan
Adiak-Adiak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta WR I Bapak Drs. H.
Suryan A. Jamrah, MA, Plt. WR II Bapak Dr. H. Ahmad Supardi, MA,
dan WR III Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SUSKA Riau beserta WD I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL,
WD II Bapak Wahidin, M.Ag, dan WD III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai ketua Jurusan Hukum
Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag sebagai Seketaris
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing skripsi yang
telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sehingga skripsi ini
dapat penulis selesaikan dengan baik.
iii
6. Bunda Mardiana, MA selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah
memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh
perkuliahan di UIN SUSKA Riau.
7. Perpustakaan UIN SUSKA Riau yang telah memberikan fasilitas berupa
buku sebagai rujukan dalam penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis
jadikan bekal dalam penulisan Skripsi ini.
9. Keluarga besar Mahad Al-Jami’ah UIN SUSKA Riau yang telah
memberikan dorongan dan semangat serta selalu membersamai penulis
selama menjalani perkuliahan di UIN SUSKA Riau.
10. Kelurga besar FK-MASSYA (Forum Kajian Mahasiswa Syariah dan
Hukum) yang telah banyak mengajarkan kebaikan pada penulis dan selalu
menjadi tempat diskusi yang hangat bagi penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis di lokal Hukum Keluarga B 2015 yang selalu setia
bersama-sama dalam T{alabu al-‘Ilmi dan Fastabiqu al-Khaira>t semoga
Allah memberkahi kawan-kawan semua.
12. Ustadz-ustadzah, guru-guru, senior, para sahabat dan teman-teman penulis
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu persatu.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
iv
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, dan bagi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari para
pembaca, semoga Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la> meridai usaha penulis. A>mi>n ya>
Rabbal ‘A>lami>n.
Pekanbaru,17 Safar 1441 H16 Oktober 2019 M
JOSHUA SUHERMANNIM. 11521104436
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDULHALAMAN PERSETUJUANPENGESAHANPENGESAHAN PERBAIKANABSTRAKMOTTOKATA PERSEMBAHANPEDOMAN TRANSLITERASIKATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI............................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1B. Batasan Masalah.......................................................................... 6C. Rumusan Masalah........................................................................6D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.................................................... 7E. Kerangka Teoritik........................................................................ 7F. Metode Penelitian........................................................................ 11G. Sistematika Penulisan.................................................................. 13
BAB II BIOGRAFI IBNU H{AZM DAN GAMBARAN HUKUMPERKAWINAN DI INDONESIA.................................................. 15A. Riwayat Hidup Ibnu H{azm.......................................................... 15B. Pendidikan Ibnu H{azm.................................................................19C. Guru dan Murid Ibnu H{azm.........................................................19D. Karya-Karya Ibnu H{azm..............................................................21E. Mazhab Ibnu H{azm......................................................................23F. Pandangan Ulama Terhadap Ibnu Hazm..................................... 25G. Dasar-Dasar Metode Istinbat} Ibnu H{azm................................... 26H. Hukum Perkawinan di Indonesia.................................................37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SAKSI ........... 40
A. Talak............................................................................................401. Pengertian Talak.................................................................... 402. Dasar Hukum Talak............................................................... 423. Rukun dan Syarat Talak.........................................................444. Macam-Macam Talak............................................................ 47
vi
B. Saksi............................................................................................ 551. Pengertian Saksi.....................................................................552. Dasar Hukum Saksi................................................................563. Syarat-Syarat Saksi................................................................ 58
BAB IV RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGANHUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANGSAKSI DALAM TALAK............................................................... 63A. Saksi dalam Talak Menurut Ibnu H{azm dan Hukum
Perkawinan di Indonesia............................................................. 631. Pendapat Ibnu H{azm Tentang Saksi dalam Talak..................632. Saksi dalam Talak Menurut Hukum Perkawinan
di Indonesia............................................................................ 68B. Relevansi Pendapat Ibnu H{azm dengan Hukum Perkawinan
di Indonesia................................................................................ 70
BAB V PENUTUP....................................................................................... 90
A. Kesimpulan................................................................................. 90B. Saran........................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam sebagai Agama yang rahmatan li> al-‘a>lami>n, yaitu rahmat bagi
seluruh alam mengatur tentang perkawinan dengan sangat teliti dan
terperinci, Islam mengatur perkawinan dengan sedemikian rupa untuk
membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya
yang mulia diantara makhluk Allah lainnya. Hidup berpasang-pasangan
adalah naluri semua makhluk Allah termasuk manusia.1 Sebagaimana Allah
Subh}a>nahu wa Ta’a>la> berfirman:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”. (QS. az|-Z|a>riya>t [51] : 49)2
Walaupun pada dasarnya perkawinan itu disebut sebagai mi>s|a>qan
ga>liz{an (ikatan yang sangat kuat) tetapi ada saat-saat tertentu dimana ikatan
itu akan lepas, karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk
juga perkawinan. Jika kebahagian dan ketenangan yang menjadi salah satu
tujuan perkawinan tidak mampu lagi diwujudkan dalam sebuah rumah
tangga, Islam memberikan solusi sebagai jalan keluar terakhir setelah
dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
1 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 12.
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika,2016), h. 522.
2
tersebut, yakni melalui perceraian (Talak). Talak harus dipahami sebagai
alternatif terakhir penyelesaian krisis rumah tangga, sehingga tidak boleh
dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.
Secara bahasa talak berasal dari kata قاالط-قلیط-طلق lafaz dari
masdarnya merupakan t}ala>k yang artinya melepaskan atau menceraikan.3
Sedangkan menurut pengertian syarak yaitu:
٤.ةالرابطة الزواج وإنهاء العالقة الزوجي حل
Artinya: Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
istri.
Agama mensyariatkan pernikahan untuk memenuhi kemaslahatan
hamba, baik dalam bidang duniawiyah maupun dalam bidang di>niyah, maka
disyariatkannya talak adalah untuk menyempurnakan pernikahan. Karena
apabila suami istri sudah tidak dapat hidup rukun dan damai lagi, lantaran
berlainan tabiat dan bertentangan kemauan, maka tentulah harus diadakan
jalan keluarnya.5
Walaupun talak disyariatkan dalam Islam namun talak merupakan
perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la. Oleh karena
itu, sebisa mungkin seseorang harus menghindari terjadinya talak dalam
rumah tangga, sebagaimna Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
3 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah,2010), h. 239.
4 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Muassasah ar-Risa>lah, 2002), Cet. Ke-1, Jilid 2,h. 261.
5 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, (Semarang: PustakaRizki Putra, 2011), h. 153.
3
وجل م قال أبغض الحالل إلى اهللا عز ى اهللا عليه وسل بي صل عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن الن ٦داود)( رواه أبو .الطالق
“Dari Ibnu Umar Rad{iyalla>hu ‘Anhuma> dari Nabi S{alla>llahu ‘Alaihi
wa Sallam bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah ‘Azza
wa Jalla adalah talak”. (H.R. Abu Daud)
Berkaitan dengan hukum talak jumhur fuqaha>’ telah sepakat bahwa
rukun dan syarat talak itu ada tiga yaitu, yang mengucapkan talak (suami),
yang ditalak (istri) dan lafaz talak (s}igat) yang masing-masing memiliki
syarat untuk bisa diterimanya talak tersebut.7
Namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa ada syarat tambahan
untuk sahnya talak, yaitu hadirnya dua orang saksi yang adil saat
mengucapkan ikrar talak. Jika tidak, maka talak tidak jatuh. Pendapat ini
berdasarkan makna zahir surah at}-T{ala>q ayat dua yaitu:
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilahmereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik danpersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu danhendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlahdiberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan
6 Abu Daud, Sunan Abi> Da>ud, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 226. Hadits ini shahihmenurut Al-Hakim dan az}-Z{ahabi.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011),Cet. Ke-3, h. 214.
4
hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akanMengadakan baginya jalan keluar”. (QS. at}-T{ala>q [65] : 2)8
Sebagaimana Ibnu H{azm yang bermazhab Z{ahiriyah9 mengemukakan
pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha>’ tentang saksi dalam talak,
seperti disebutkannya dalam kitab al-Muh}alla>:
، وقال يا لحدود اهللا تعالىق ولم يشهد ذوي عدل، أو رجع ولم يشهد ذوي عدل، متعد وكان من طل ١٠.مرنا فهو رد أمن عمل عمال ليس عليه م اهللا عليه وسل ىرسول اهللا صل
Artinya: Siapa yang menjatuhkan talak dan tidak disaksikan oleh dua oarangsaksi yang adil atau rujuk dan tidak disaksikan oleh dua orang saksiyang adil maka dia sudah melampaui batasan Allah Subh}a>nahu waTa’a>la, padahal Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai denganketentuan kami, maka perbuatannya tertolak.
Dari penjelasan Ibnu H{azm di atas dapat dipahami bahwa
menghadirkan saksi saat menjatuhkan talak adalah suatu kewajiban, sehingga
apabila suami menjatuhkan talak namun tidak menghadirkan dua orang saksi
yang adil maka dia telah melanggar batasan Allah dan perbuatannya tersebut
tidak sah.
Indonesia yang terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam telah menjadikan sebagian hukum-hukum Islam sebagai
hukum positif dalam mengatur kehidupan bernegara terutama hukum-hukum
ahwa>l al-syakhs}iyyah. Hukum perkawinan di Indonesia telah diatur
8 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 558.
9 Az}-Z{ahiri atau Z{ahiriyah adalah salah satu mazhab fikih dalam lingkup Ahlu Sunnahdengan imamnya Da>ud bin Khalaf az}-Z{ahiri, yang paling menonjol dari mazhab ini adalah metodeliteralnya dalam penggalian hukum dari nas} (al-Qur’an dan Sunah) mereka hanya memandangzahirnya saja dan menolak penggunaan qiyas secara keseluruhan.
10 Ibnu H}azm, Al-Muh}alla> Bi al-As|ar, (Beirut: Da>r al-Fikr, t,th), Juz 10, h. 251.
5
sedemikian kompleks dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan dalam buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia termasuk
didalamnya mengatur tentang tatacara perceraian. Dalam undang-undang
tersebut diatur bahwa perceraian harus dilaksanakaan di depan sidang
Pengadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.11
atau sebagaimana disebutkan pada pasal 115 Buku I Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia yaitu:
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”.12
Dengan adanya undang-undang ini suami tidak lagi dapat
menjatuhkan talak kecuali di depan sidang Pengadilan Agama, ini berbeda
dengan apa yang telah disepakati oleh jumhur bahwa suami dapat
menggunakan hak talaknya kapan saja dan dimana saja asalkan syarat-
syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada kewajiban untuk mengucapkannya di
11 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,(Jakarta: Laksana, 2013), Cet. Ke-1, h. 22.
12 Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1999), h. 56.
6
depan sidang Pengadilan Agama. Kaitannya dengan apa yang telah
disebutkan sebelumnya adalah apakah pendapat Ibnu H{azm tentang wajibnya
menghadirkan saksi dalam talak dapat mendukung dan relevan dengan
hukum perkawinan di Indonesia yang mengharuskan perceraian di depan
sidang Pengadilan Agama.
Berdasarkan paparan diatas dapat ditemukan perbedaan pendapat
ulama tentang keberadaan saksi dalam talak, hukum perkawinan di Indonesia
sendiri mengatur lain tentang tatacara perceraian di Indonesia. Dengan
munculnya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
tentang saksi dalam talak, sehingga dapat diketahui pendapat mana yang lebih
kuat dan mendekati kepada kehendak syarak. Penelitian ini penulis tuangkan
dalam skripsi dengan judul RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM
DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG
SAKSI DALAM TALAK.
B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan mengingat luasnya masalah yang
timbul dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini difokuskan hanya pada relevansi pendapat Ibnu H{azm dengan
hukum perkawinan di Indonesia tentang saksi dalam talak.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa pokok
masalah yang akan dirumuskan dan menjadi bahasan utama yaitu:
7
1. Bagaimana kedudukan saksi dalam talak menurut Ibnu H{azm dan hukum
perkawinan di Indonesia?
2. Apakah ada relevansi pendapat Ibnu H{azm dengan hukum perkawinan di
Indonesia tentang saksi dalam talak?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui kedudukan saksi dalam talak menurut Ibnu H{azm dan
hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibnu H{azm dengan hukum
perkawinan di Indonesia tentang saksi dalam talak.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut
ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur
bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat Islam, dari semua kalangan
untuk mengetahui hukum saksi dalam talak.
E. Kerangka Teoritik
Islam adalah agama kemanusian, ajaran-ajarannya senantiasa sejalan
dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia
baik maka Islam akan membolehkannya bahkan menganjurkan dan apa yang
8
membuat manusia celaka atau menderita maka Islam akan melarangnya.
Persoalannya bagaimana manusia mengungkap ajaran Islam itu dan
menyingkap makna yang terkandung didalamnya, dalam konteks itulah Islam
membuat berbagai formulasi ajaran tentang berbagai persoalan kehidupan dan
mengatur serta mengkategorikannya sesuai dengan tingkat ketegasan dalil
yang yang digunakan untuk perintah dan larangan tersebut.
Berbicara tentang dalil, yang menjadi rujukan utama dalam hukum
Islam adalah al-Qur’an dan Hadis. Namun kenyataan menunjukkan bahwa
kedua sumber dimaksud terdiri dari lafaz-lafaz bahasa Arab yang kadang
dalam suku katanya mempunyai banyak arti, ada lafaz yang dari satu sisi
dipandang sebagai hakikat tetapi disisi lain dipandang sebagai majas, ada
lafaz dalam bentuk mutla>q dan ada yang muqayyad, disamping itu ada lafaz
yang berbentuk perintah dan ada pula yang berbetuk larangan, dan lain
sebagainya. Sehingga dalam memahami lafaz-lafaz tersebut banyak terdapat
perbedaan pendapat (ikhtila>f) dikalangan ulama fikih.13
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam
memahami masalah furu’ yaitu:
1. Perbedaan dalam hal qira’a>t
2. Adanya ketidaksamaan dalam menerima informasi hadis
3. Tidak adanya kesepakatan ulama tentang eksistensi hadis
4. Adanya perbedaan dalam memahami nas} dan interpretasinya
13 Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-5, h.129.
9
5. Adanya lafaz yang musytarak
6. Adanya ta’a>rud al-adillah
7. Tidak adanya nas} dalam suatu masalah
8. Berbeda dalam kaidah us}uliyyah.14
Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah pendapat Ibnu H{azm
tentang wajib adanya saksi dalam talak kemudian bagaimana relevansinya
dengan hukum perkawinan di Indonesia. Sebenarnya persoalan persaksian
talak merupakan salah satu persoalan hukum yang secara tersurat terdapat
dalam al-Qur’an surah at}-T{alaq ayat dua, hanya saja hakikat perintah
mengenai persaksian dalam talak ini harus dicari penjelasannya dengan jalan
ijtihad. Adanya peluang ijtihad dalam memahami maksud dari ayat tersebut
memunculkan perbedaan pandangan dikalangan ulama dengan
argumentasinya masing-masing. Jumhur fuqaha>’ memahami amar yang
terdapat dalam lafaz (وأشھدوا) bukanlah menunjukkan wajib dan ditujukan
hanya kepada rujuk, sedangkan Ibnu H{azm memahami bahwa setiap amar
adalah wajib dan dalam ayat ini ditujukan kepada talak dan rujuk.15
Hukum perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum
syarak semenjak adanya umat Islam di Indonesia ini. Aturan syarak tersebut
terdapat dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih menurut mazhab
14 Mustafa Sa’id al-Kha>n, As|ar al-Ikhtila>f fi al-Qawa>’id al-Us}uliyyah fi Ikhtila>f al-Fuqaha>’, (Beiru: Muassasah ar-Risa>lah, 1982), Cet. Ke-2, h. 38-117.
15 Lihat kitab Al-Umm karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Cetakan Dar al-Wafa’Tahun 2000 Juz 8, halaman 191 dan kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm cetakan Dar al-Fikr t,thJuz 10, halaman 251.
10
Sya>fi’i>.16 Aturan syarak tersebut telah meresap dan hidup ditengah
masyarakat, namun kenyataannya hukum positif yang mengatur tatacara
perceraian yang termasuk kedalam hukum perkawinan tersebut, berbeda
dengan hukum yang dipahami oleh masyarakat yaitu hukum perceraian
berdasarkan mazhab Sya>fi’i>, menurut Imam Sya>fi’i> bahkan empat imam
mazhab yang masyhur talak dapat jatuh tanpa harus di Pengadilan dan tanpa
harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana menurut Ibnu H{azm.
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan
konseptual (coceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute
approach). Pendekatan konseptual (coceptual approach) digunakan dalam
membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian manakala
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada terkait masalah yang
dipahami. Sedangkan pendekatan undang-undang (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.17
Penggunaan pendekatan undang-undang dalam penulisan ini adalah
ditunjukkan dengan adanya proses menelaah ketentuan hukum perceraian
yang ada didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan penggunaan
pendekatan konseptual ditunjukkan dengan adanya pemaparan dan analisa
16 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum IslamKontemporer di Indonesia, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-2, h. 47.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Publishing, 2010), h. 93.
11
terhadap konsep-konsep talak dari berbagai perspektif yaitu perspektif jumhur
fuqaha>’, perspektif Ibnu H{azm dan perspektif hukum perkawinan di
Indonesia.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaanya atau cara untuk
memperoleh data yang diinginkan.18 Adapun metode dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) yaitu riset yang dilakukan dengan jalan
membaca buku-buku/ majalah dan sumber data lainnya didalam
perpustakaan atau menjadikan bahan pustaka sebagi sumber.19 Jenis
penelitian ini disebut jenis hukum normatif, yaitu metode hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data primer dan
sekunder.
2. Sumber Data
Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung
keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sangat
18 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,2009), h. 2.
19 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1997), h. 13.
12
diperlukan dalam melakukan penelitian atau istilah lain data yang utama.
Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai
data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.20 Dalam
penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari kedua sumber tersebut
yaitu:
a. Data primer yaitu: kitab Al-Muh{alla> bi al-As|a>r, karya Ibnu H{azm,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
b. Data sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedia Islam dan buku-buku fikih
yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar
untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk motode pengumpulan data
dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan
pertama oleh peneliti adalah:
a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok
permasalahan.
b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data
yang lengkap sekaligus terjamin.
c. Mencatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu
diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas.
20 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke-2, h. 72.
13
4. Teknik Analisa Data
Setelah sejumlah data yang ada telah berhasil penulis simpulkan
dan telah tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan
menggunakan metode analisis (conten analysis) yaitu mempelajari dan
memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi dan budaya,
kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diteliti. Metode ini akan
penulis gunakan pada Bab IV mengenai kedudukan saksi dalam talak
menurut Ibnu H{azm dan hukum perkawinan di Indonesia.
5. Metode Penulisan
Setelah memperoleh data-data tersebut, maka penulis berikutnya
mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:
a. Deskriptif Analitik
Mengumpulkan data-data secara kongkrit serta menyusun,
menjelaskan, dan menganalisa sehingga dapat disusun sesuai dengan
kebutuhan penulisan skripsi.
b. Deduktif
Menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan
tulisan lalu dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
G. Sistematika Penulisan
Agar penulisan penelitian ini sistematis, maka perlu dipergunakan
sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah, maka
penulis menyusun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab
14
terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penyusunannya adalah
sebagai berikut:
BAB I Berisikan pendahuluan yang menggambarkan latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II Berisi tentang biografi Ibnu H{azm mulai dari riwayat hidup,
pendidikan, guru dan murid, karya-karya, mazhab, pandangan
ulama terhadapnya dan dasar-dasar metode istinbath hukum
Ibnu Hazm serta gambaran umum tentang hukum perkawinan di
Indonesia
BAB III Berisi tinjauan umum tentang talak dan saksi yang terdiri dari
pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak dan
macam-macam talak. Kemudian pengertian saksi, dasar hukum
saksi dan syarat-syarat saksi.
BAB IV Merupakan pembahasan dan hasil penelitian yang berisi tentang
kedudukan saksi dalam talak menurut Ibnu H{azm dan hukum
perkawinan di Indonesia, kemudian relevansi pendapat Ibnu
H{azm dengan hukum perkawinan di Indonesia.
BAB V Merupakan penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka
15
BAB II
BIOGRAFI IBNU H{AZM DAN GAMBARAN TENTANG HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA
A. Riwayat Hidup Ibnu H{azm
Salah seorang tokoh ilmuwan muslim yang cukup masyhur baik
dikalangan internal muslim maupun dikalangan pengkaji Islam Barat klasik
maupun modern adalah Ibnu H{azm, nama lengkapnya adalah Al- Hafiz} Abu>
Muh}ammad ‘Ali> bin Ah}mad bin Said bin H{azm bin Ghalib bin Shalih bin
Khalaf al-Fari>si> al-Yazi>di> al-Qurt}ubi> al-Andalusi> az}-Z{ahiri.21 Dalam literatur
lain Abu> Muh}ammad ‘Ali> Ibn Ah}mad Ibn Said Ibn H{azm Ibn Galib Ibn S}aleh
Ibn Khalaf Ibn Ma’dan Ibn Sufyan Ibn Yazi>d Ibn Abi> Sufyan Ibn Harb Ibn
Umayyah Ibn Abd Syams al-Umawiyah al-Fari>si> al-Qurt}ubi> az}-Z{ahiri.22
Nama panggilannya adalah Abu> Muh}ammad, ia dilahirkan pada hari
terakhir bulan Ramadan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum
munculnya matahari di Qurt}ubah (Cordova), Spanyol.23 Atau lebih tepatnya
pada hari Rabu, 30 Ramadan 384 H/ 7 November 994 M, pada masa Hisyam
al-Muayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al-H{akam al
Muntas}ir. Kakeknya Yazi>d, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari
garis para kakeknya dan berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf bin Ma’dan
21 Ibnu Taimiyah, Naqdu Maratib al-Ijma’, (Beirut: Da>r Ibnu H{azm, 1998 ), Cet. Ke-1, h.15.
22 Ibnu H{azm, Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l Al-Ah}ka>m, (Kairo: Da>r al-H{adi>s|, 2005), h. 6.
23 Faruq Abdul Mu’thi, Ibnu H{azm Az}-Z}ahiri, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992),Cet. Ke-1, h. 8.
16
adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama Musa Ibnu
Nusair dalam bala tentara penaklukan pada tahun 93 H, sehingga dari garis
nasabnya dapat diketahui bahwa ia mempunyai garis keturunan yang berasal
dari keluarga Persia.24
Sejarawan dan intelektual pada umumnya menyebut Ibnu Ḥazm
dengan tambahan nasab al-Qurṭubi> atau al-Andalusi>, namun Ibnu Ḥazm
sebenarnya tidak begitu nyaman menggunakan nasab al-Andalusi> ataupun al-
Qurṭubi>, ia lebih nyaman sebagai orang Persia karena memang nenek
moyangnya dari Arab-Persia. Oleh karena itu, Abu> Zahrah25 tidak
menggunakan dua kata al-Jinsiyyah diatas, cukup dengan titel Ibnu Ḥazm
atau dengan nama panjangnya, yakni ‘Ali> bin Ah}mad bin Said bin Ḥazm
dengan kunyah Abu> Muh}ammad.26
Kalangan sejarahwan mengisahkan bahwa keturunan atau keluarga
Ibnu H{azm berasal dari keturunan bangsawan, terpandang sekaligus memiliki
kedudukan dan status sosial terhormat di masanya. Ibnu H{azm di masa
kecilnya dididik dan dibesarkan dalam serba kemewahan istana. Menurut Al-
Fath Ibnu Khaqan seperti dikutip Mahmud Ali Himayah, bahwa bani H{azm
termasuk keluarga atau generasi-generasi berilmu, beradab, mulia dan
24 Ahmad Tajuddin Arafat, Filsafat Moral Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa as-Siyar Fi Mudawati an-Nufus, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni 2013, h. 54.
25 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zahrah(1315-1394 H), merupakan seorang ulama Mesir yang memiliki keahlian dibidang Tafsir danFikih.
26 Zuhri, Ibnu Hazm al-Andalusi dan Khilafah, Esensia. Vol 17, No. 2, Oktober 2016. h.141.
17
terpandang. Ayahnya bernama Ah}mad Ibnu Sa’id (dalam leteratur lain
bernama Abu> Umar Ah}mad), termasuk golongan orang cerdas yang
memperoleh kemuliaan dibidang ilmu dan kebudayaan, beberapa orang dari
kalangan keluarga mereka menduduki jabatan strategis dimasanya dan
memiliki wibawa serta pengaruh yang luas di Cordova (Spanyol).27
Kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibn H{azm bersama
keluarganya tidaklah selalu ia rasakan. Segala cobaan, fitnah dan kekerasan
hidup pernah menimpanya, terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan
dari satu penguasa kepenguasa lainnya. Ibnu H{azm bersama keluarganya
merasakan pahit getir kehidupan, terutama pada awal masa mudanya. Hal ini
digambarkan dalam perkataannya:
“Setelah kepemimpinan Hisyam al-Muayyad, kami mendapatkanbanyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara.Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit utang serta diterpa banyakfitnah sampai wafatnya ayah kami (Ah}mad bin Sa’id) yang menjadimenteri, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu setelah waktu ‘As}ar,dua malam terakhir bulan Z|ulqa‘idah 402 H/ Juni 1013 M”.
Pada bulan Z|ulqa’idah 401 H saudara satu-satunya yang bernama Abu>
Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang
meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya
yang bernama Na’ma yang meninggal pada tahun 403 H. Pada akhirnya, ia
27 Muh Said HM, Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm Tentang Kesejahteraan TenagaKerja, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah. Vol 3, No. 2, Desember 2016, h. 202.
18
pun meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H yang kala itu sedang
diguncang prahara perang saudara dan menetap di Almeria dan Jativa.28
Ibn H{azm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama
yang mulia dan berilmu. Menurut beberapa sarjana kontemporer seperti
Nuruddin al-Khadimi (Tunisia), Muhammad ‘Abid al-Jabiri (Maroko) dan
Abu> Zahrah (Mesir) menganggap Ibnu H{azm sebagai sebagai salah seorang
tokoh pembaharu dalam Islam. Bahkan Abdul Hadi Abdurrahman dalam
bukunya The Authority of the text menobatkannya sebagai Mega Mujtahid
dalam sejarah fikih Islam.29
Ibnu H{azm menghabiskan masa tua di desanya, Mint Lisym. Di sana
ia menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah
pedalaman. Ia mengajarkan ilmu hadis dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan
mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang hingga sempurnalah
karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu. Pada malam senin tanggal 28
Sya’ban tahun 456 Hijriyah/ 15 Juli 1064 Masehi, Ibnu H{azm meninggal
dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan
dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan, Ibnu H{azm meninggal
dalam umurnya yang ke 72 tahun.30
28 Ahmad Tajuddin Arafat, Op.Cit, h. 55.
29 Noer Yasin, Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani, (Malang: UINMaliki Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 7.
30 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007),Cet. Ke-2, h. 677.
19
B. Pendidikan Ibnu H{azm
Ibnu H{azm pada masa awal kehidupannya belajar sebagaimana
kebiasaan anak-anak pejabat negara pada masa itu, seperti menghafal syair-
syair dan al-Qur’an serta belajar menulis yang diasuh oleh pelayan-pelayan
wanita yang ada di istana.31
Pada usia remaja Ibnu H{azm selalu diajak oleh ayahnya menghadiri
majelis-majelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah al-Mans}u>r
dan dihadiri pula oleh ahli-ahli syair dan ilmuwan. Ia juga belajar kepada
seorang guru pilihan ayahnya yang sangat alim dan wara’ yaitu Abu> al-
Husain Ibnu ‘Ali> al-Fari>si>. Ibnu H{azm selalu disamping guru pilihan ayahnya
itu, seorang guru yang melenyapkan dorongan-dorongan nafsu dari murid
muda seperti Ibnu H{azm. Ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria
menurut Ibnu H{azm adalah merupakan hal yang biasa di dalam dunia
pendidikan di Andalusia. Dengan kecepatan daya tangkap, kekuatan daya
ingat dan kecermatan pemahamannya yang dikaruniakan oleh Allah
Subh}a>nahu wa Ta’a>la Ibnu H{azm menjadi pemuda yang nyaris mengungguli
guru-gurunya.
C. Guru dan Murid Ibnu H{azm
1. Guru-guru Ibnu H{azm
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setelah memasuki usia
remaja, Ibnu H{azm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang guru, yaitu
31 Faruq Abdul Mu’t}i, Op.Cit, h. 15.
20
Abu al-Husain Ibnu ‘Ali> al-Fari>si>. Pergaulannya dengan gurunya ini
banyak mempengaruhi pembentukan kepribadiaannya, dari gurunya ini ia
mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan bimbingan serta teladan
pengamalan ilmu-ilmu yang diketahuinya.
Ibnu H{azm belajar dari para ulama yang memiliki keluasan
pengetahuan dalam agama semisal hadis, fikih, logika dan lainnya.
Adapun diantara guru-gurunya adalah:
a. Dalam Hadis, Ah}mad bin Muh}ammad al-Jaswar (wafat tahun 401 H),
guru pertama Ibnu H{azm, al-H{amdani dan Abu> Bakar Muh}ammad
Ibnu Isha>q.
b. Dalam Fikih, ‘Ali> Abdulla>h al-‘Azdi>, al-Fa>qih Abu> Muh}ammad Ibnu
Duhun al-Maliki> dan Abu> al-Khayyar Mas’ud bin Sulaima>n bin
Maflat az}-Z{ahiri>.
c. Dalam Logika dan Akhlaq, Muh}ammad bin al-Hasan al-Maz|haji
(wafat tahun 400 H), Abu> al-Qa>sim Abdurrahma>n bin Abu> Yazi>d al-
Mis}ri>, Abu> al-Husain al-Fari>si>, sahabat sekaligus guru panutan Ibnu
H{azm, Abu> Muh}ammad ar-Rahuni dan Abdulla>h bin Yusuf bin
Nami.32
Ibnu H{azm juga belajar secara formal di Madrasah Andalusiah. Di
antara tokoh-tokoh ulama yang mengajar di Madrasah tersebut sekaligus
menulis banyak buku-buku, baik dibidang hadis, ahkam al-Qur’an, tarikh
32 Ahmad Tajuddin Arafat, Op.Cit, h. 56-57.
21
dan fikih yang pada giliranya sangat mempengaruhi pola pikir Ibnu H{azm
dalam berijtihad dengan metode pembahasan bi al-As|ar (riwayat shahabat)
ialah Muh}ammad Ibn Aiman, Ah}mad Ibnu Khalid, dan Qa>sim Ibn Asbagh
al-Qurt}ubi>.
2. Murid-Murid Ibnu H{azm
Adapun murid-murid Ibn H{azm yang terkenal diantaranya adalah
putranya sendiri yaitu Abu> Ra>fi’ al-Fadhl, kemudian Muh}ammad bin Abu>
Nas}r al-Humaidi (420-488 H) yang menyebarkan mazhab Z{ahiri ke
Masyriq setelah Ibnu H{azm wafat serta al-Qa>d}i Abu> al-Qa>sim Sa’id bin
Ah}mad al-Andalusi> (wafat tahun 463 H) dan masih banyak yang lainnya.
Ibnu ‘Arabi> sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Z{ahiri setelah
wafatnya Ibn H{azm.33
D. Karya-karya Ibnu H{azm
Diantara keistimewaan Ibnu H{azm adalah karya-karyanya yang
banyak dan beragam sehingga banyak pencari ilmu belajar dari karya-
karyanya itu. Ibnu H{azm mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam
ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas
untuk mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi maupun Nasrani.
Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnu H{azm menguasai bidang tafsir, hadis,
fikih, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq.
33 Ibid.
22
Sa’id meriwayatkan dari Abu> Ra>fi’ bahwa ayahnya (Ibnu H{azm)
mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadis, us}ul, perbandingan
agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah
karyanya tersebut mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas
yang ditulis olehnya sendiri.34
Adapun karya-karya Ibnu H{azm diantaranya adalah:
1. Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m
Kitab ini berbicara tentang usul fikih terutama usul fikih Z{ahiri,
dalam cetakan Da>r al-H}adi>s| terdiri dari satu jilid tebal yang didalamnya
terdapat delapan juz.
2. Al-Muh}alla> bi al-As|a>r
Kitab ini terdiri atas 11 juz dalam 8 jilid tebal (dalam cetakan Da>r
al-Kutub al-‘Ilmiyyah 12 jilid), yang berisi tentang fikih beserta
argumentasinya. Kitab ini merupakan karya terakhir Ibnu H{azm dan
menjadi rujukan utama dikalangan penganut mazhab Z{ahiri sampai
sekarang.
3. Al-Fas}l fi> al-Mila>l wa al-Ahwa’ wa an-Niha>l
Kitab ini berbicara mengenai sekte-sekte, mazhab dan agama-
agama.
34 Syaikh Ahmad Farid, Op.Cit, h. 674.
23
4. T{auq al-Hama>mah fi> Ulfah wa al-Ula>f
Kitab ini berbicara manusia dari sisi kejiwaannya yang meliputi
cinta dan para pencinta, ditulis di kota Syatihibi sekitar tahun 418 H, dan
menjadi karya Ibn Hazm yang paling banyak dikaji di Eropa.
5. Al-Akhla>q wa-Assiya>r fi> Muda>wa>t an-Nufu>s
Kitab ini berisi prinsip-prinsip perilaku utama, moralitas dan etika
serta solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan
kesempurnaan.35
Masih banyak lagi karya-karya Ibnu H{azm yang lainnya, seperti yang
disebutkankan didalam pendahuluan kitab Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m
sebanyak 32 judul kitab dan didalam buku 60 Biografi Ulama Salaf karya
Syaikh Ahmad Farid, disebutkan sebanyak 53 judul kitab. Banyaknya karya-
karya Ibnu H{azm membuktikan kedalaman ilmunya yang tidak diragukan
lagi.
E. Mazhab Ibnu H{azm
Pada awalnya Ibnu H{azm mempelajari fikih Maliki, karena mazhab
Malikilah yang berkembang di Andalusia dan menjadi mazhab resmi
pemerintah. Ibnu H{azm pernah mengatakan bahwa ada dua mazhab yang
35 Ahmad Tajuddin Arafat, Loc.Cit.
24
berkembang karena mendapat dukungan penguasa yaitu mazhab Abu Hanifah
di Timur dan mazhab Maliki di Barat.36
Kemudian dalam perjalanannya menuntut ilmu Ibnu H{azm mulai
membaca fikih mazhab Sya>fi’i> dan menemukan kritiakn-kritikan imam
Sya>fi’i> terhadap mazhab Maliki, ketika itu ia berkata “Aku mencintai Maliki,
tetapi kecintaanku terhadap kebenaran melebihi cintaku pada Maliki”.37
Setelah itu Ibnu H{azm, pindah dari mazhab Maliki kepada mazhab Sya>fi’i>,
Ibnu H{azm terus mendalami mazhab Sya>fi’i> dan mazhab ulama-ulama di
Irak.
Walaupun sangat mengagumi namun ternyata Ibnu H{azm juga tidak
puas dengan mazhab Sya>fi’i> karena menerima qiyas sebagai salah satu
sumber penetapan hukum, nampaknya Ibnu H{azm tidak setuju dengan
pendapat ini, akhirnya Ibnu H{azm berpindah mazhab kembali dan lebih
condong kepada mazhab az}-Z{ahiri dengan imamnya Da>ud ‘Ali> bin Khalaf al-
Asbahani (202-270 H), karena mazhab inilah satu-satunya yang sesuai
dengan Ibnu H{azm yang ingin mengunkapkan hukum dari al-Qur’an dan as-
Sunah tanpa menggunakan qiyas, sehingga orang-orang mengatakan bahwa
36 M Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet.Ke-2, h. 235.
37 Faruq Abdul Mu’t}i, Op.Cit, h. 23.
25
Ibnu H{azm adalah penganut mazhab Z{ahiri namun ada juga yang mengatakan
kebetulan saja jalan pikiran kedua imam itu sama.38
F. Pandangan Ulama Terhadap Ibnu Hazm
Dalam buku 60 biografi ulama salaf Syaikh Ahmad Farid mengutip
pernyataan Abu Hamid al-Ghazali yang mengatakan bahwa “Aku
menemukan kitab yang membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala,
yang ditulis oleh Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi. Kitab tersebut
menunjukkan kuatnya hafalan pengarangnnya dan tingginya kecerdasannya”.
Syaikh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, “Ibnu Hazm termasuk
golongan ulama mujtahid. Aku tidak pernah melihat kitab yang
membicarakan ilmu keislaman seperti kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan
kitab Al-Mughni karya Syaikh Muwaffiquddin”.39
Selain sanjungan dan pujian yang diberikan oleh beberapa ulama,
Ibnu Hazm juga mendapat beberapa kritikan dari para ulama pada masanya
maupun pada masa setelahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Az-Zahabi
“Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisan
dan penanya. Namun ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara
terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari
apa yang ia lakukan, karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan
bahkan pernah dibakar”.
38 M Ali Hasan. Op.Cit, h. 237.
39 Syaikh Ahmad Farid, Op.Cit, h. 665.
26
Ibnu Kasir juga pernah mengatakan, “Ibnu hazm sering menyerang
para ulama dengan pena dan lisannya. Hal ini menimbulkan kedengkian
dihati orang-orang pada zamannya mereka selalu tidak senang kepadanya dan
memprovokasi para raja untuk ikut tidak senang terhadapnya”.40
G. Dasar-Dasar Metode Istinbat} Ibnu H{azm
Ibnu H{azm dalam menggali suatu hukum mendasarkan pada zahirnya
nus}us yakni al-Quran dan Sunah, dalam prakteknya Ibnu H{azm menggunakan
empat dasar dalam menggali suatu hukum, sebagaimana tergambar dari
perkataannya:
كالم رسول ااهللا ونص ، القرانها أربعة وهي: نص وأن ، تي ال يعرف شئ من الشرائع إالمنهااألصول ال ، واترالم نقل الثقات أو الت الس عليهعنها صح ما هو عن اهللا تعلى مم م, الذي إن ى ااهللا عليه وسل صل
٤١.إال وجها واحدايحتملأو دليل منها ال، ةوإجماع جميع علماء األم
Artinya: “Hukum syarak tidak akan dapat diketahui kecuali dengan empatdasar yaitu: nas} al-Qur'an, nas} kalam Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihiwa Sallam yang sebenarnya datang dari Allah juga yang sahih kitaterima dari padanya dan diambil dari orang-orang kepercayaan atauyang mutawatir, ijmak oleh semua ulama umat dan suatu dalil yanghanya mengandung satu pengertian”.
Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang
digunakan oleh Ibnu H{azm dalam mengistinbatkan suatu hukum adalah
sebagai berikut:
40 Ibid, h. 670-671.
41 Ibnu H{azm, Op.Cit, 2005, h. 86-87.
27
1. Al-Qur’an
Menurut Ibnu H{azm tidak ada ayat mutasyabihat selain Fawa>tih
As-Suwa>r, karena semua ayat al-Qur’an adalah jelas dan terang maknanya
bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan
mengetahui hadis yang sahih.42
Al-Qur’an adakalanya dijelaskan oleh al-Qur’an sendiri seperti
hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris dan adakalanya
dijelaskan oleh sunah seperti tatacara salat, puasa, zakat dan haji, maka
ketika itu sunah menjadi penjelas bagi al-Qur’an.43 Sebagaimana Allah
‘Azza wa Jalla berfirman:
“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab, dan Kami
turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkan”. (QS. An-Nahl [16]: 44)44
Penjelasan al-Qur’an terhadap al-Qur’an kadang masih
membutuhkan takhsis karena masih belum jelas atau berbentuk umum,
42 Noer Yasin, Op.Cit, h. 19.
43 Muh}ammad Abu> Zahrah, Tarekh al-Maza>hib al-Isla>miyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, th), h. 546.
44 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 272.
28
sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ibnu H{azm
membagi ayat-ayat yang mengkhususkan itu menjadi dua yaitu:
a. Ayat yang menjelaskan bersamaan turunnya dengan ayat yang
dijelaskan, ini disebut takhsis.
b. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang
dijelaskan, ini disebut nasakh.45
Menurut Ibnu H{azm nasakh adalah pengecualian terhadap
keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah
dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang
membolehkan menikahi wanita ahli kitab.
Dalam memahami sebuah nas} Ibnu H{azm selalu melihat dari sisi
zahirnya. Nas} yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang
zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang
zahir. Oleh karena ini juga konsep fikih yang diusung oleh Ibnu H{azm
disebut dengan fikih az}-Z{ahiri.46
2. Sunah
Sumber hukum kedua menurut Ibnu H{azm adalah Sunah, yaitu
meliputi perkataan, perbuatan dan taqri>r Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa
Sallam. Sunah qauliyah yang berupa perintah (awa>mir) dan larangan
(nawa>hi) harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada
45 Muh}ammad Abu> Zahrah, Loc.Cit.
46 M. Lathoif Ghozali, Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam FiUshul Al-Ahkam, Jurnal hukum Islam, Vol. 01. No. 01 Maret 2009, h. 24.
29
kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Manusia tidak
diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh
tanpa ada dalil dari al-Qur’an, sunah, atau ijmak, karena yang demikian
berarti melawan kehendak Allah ‘Azza wa Jalla.47
Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi (sunah fi’liyah) hanya
berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru (uswah/ qudwah
hasa>nah). Hukum mengikutinya tidaklah wajib, kecuali sunah fi’liyah itu
berfungsi sebagai peragaan terhadap sunah qawliyah. Berkenaan dengan
persetujuan Nabi (sunah taqririyah) terhadap tindakan sahabat yang
diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, tidak
wajib mengikuti perbuatan Nabi S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam, tetapi boleh
saja mengikutinya sebagai suri teladan.48 Hal ini didasarkan pada firman
Allah ‘Azza wa Jalla:
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
47 Noer Yasin, Op.Cit, h. 20.
48 A. Halil Thahir, Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016, h. 155.
30
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah”. (QS. Al-Ah}za>b [33]: 21)49
Ibnu H{azm sebagaimana halnya mayoritas ulama, berpendapat
bahwa al-Qur’an dan sunah adalah sama-sama wahyu Allah Subh}a>nahu wa
Ta’a>la>. Sebagaimana firman-Nya:
“Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan
hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang
diwahyukan (kepadanya)”. (QS. An-Najm [53]: 3-4)50
Atas dasar itu Ibnu H{azm memformulasikan bahwa wahyu itu
terbagi dua, pertama, wahyu yang dibaca (wahyu matluw) dan susunan
redaksinya mengandung mu’jizat, itulah al-Qur’an. Kedua, wahyu yang
tidak dibacakan dan susunan redaksinya tidak merupakan mu’jizat (wahyu
marwi), yaitu berita (al-khabar) yang berasal dari Rasulullah S{alla>llahu
‘Alaihi wa Sallam. Oleh karena itu, antara al-Qur’an dan Sunah (selama
sunah itu sahih) selalu bersesuaian kandungannya dan tidak akan terjadi
kontradiksi (ta’a>ruḍ) antara keduanya.51
49 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 420.
50 Ibid, h. 526.
51 Ibnu H{azm, Op.Cit, 2005, h. 111.
31
3. Ijmak
Sumber hukum ketiga dalam beristinbat yang diakui Ibnu H{azm
adalah ijmak, namun Ibnu H{azm mengkhususkannya hanya pada ijmak
para sahabat. Sebagaimana perkataannya:
فق أن جميع الصحابة رضي اهللا عنهم ذى تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما إت وأما اإلجماع ال ٥٢غير هذا.شيأليس اإلجماع في الدين،ى اهللا عليه و سلمدانوا به عن نبيهم صل تقالوه و
Artinya: Adapun ijmak yang bisa dijadikan hujah dalam syariat adalahapa yang telah disepakati oleh seluruh sahabat Rad{iyalla>hu‘Anhum. mereka adalah orang yang berbicara langsung dandekat dengan Nabi S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam maka tidak adaijmak dalam agama kecuali ini.
Ibnu H{azm menguatkan pendapatnya, tentang kehujahan ijmak
serta keharusan tetap bersandar pada nas} walaupun dalam ijmak, dengan
ayat-ayat al-Qur’an, di antaranya yaitu:
“Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaranbaginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orangmukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telahdikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, danJahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa>’ [4]: 115)53
Ijmak menurut Ibnu H{azm adalah Ijmak yang mutawatir dan
bersambung sanadnya kepada Rasulullah, adapun ijmak yang tidak
bersandar pada nas} bukanlah Ijmak, dalam hal ini ia berkata:
52 Ibid, h. 62.
53 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 97.
32
عليه وسلم فهو منقول، و البد اهللاى كالم منه صل اإم :ذلك النص ، و عن نص الإجماع إالإذ علمه فأقره إقرارهام أو عليه سالم فهو منقول أيضا، كذلك عن فعل منه وإمامحفوظ حاضر،
الوجوهعلمه على غير هذهوكل من ادعى إجماعاولم ينكره فهي أيضا حال منقولة محفوظة،٥٤.دعواهكلفناه تصحيح
Artinya: Tidak ada ijmak melainkan karena ada nas}, nas} itu adakalanyasabda Nabi S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam, adakalanyaperbuatannya, adakalanya taqri>r-nya. Maka siapa yang mengakuada ijmak selain dari ini kami minta kepadanya untukmemperbaiki pengakuannya itu.
Bahkan Ibnu H{azm mengkritik imam Malik yang menjadikan
ijmak Ahlul Madinah sebagai hujah, hal tersebut dikarenakan, pertama,
ijmak seperti ini adalah hal yang tidak mempunyai dasar, kedua,
keutamaan Madinah hanya berlaku pada masa itu saja, ketiga, orang yang
menyaksikan wahyu adalah para sahabat, keempat, perselisihan juga
terjadi di Madinah.55
4. Ad-Dali>l
Jika dari ketiga sumber yang telah disebutkan tidak ditemukan
aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu H{azm
menempuh jalan ijtihad yaitu dengan meggunakan ad-Dali>l. Menurut Ibnu
H{azm ad-Dali>l sejatinya tidaklah berdiri sendiri diluar nas } al-Qur’an,
sunah atau ijmak, melainkan tetap berasal dan bersumber daripadanya.56
54 Ibid, h. 544.
55 M. Lathoif Ghozali, Op.Cit, h. 25.
56 A. Halil Thahir, Op.Cit, h. 156.
33
Ibnu H{azm menolak qiyas dan menegaskan bahwa ad-Dali>l
berbeda dengan qiyas, dan ia bukanlah tambahan terhadap nas } atau sesuatu
yang berdiri sendiri diluar nas } sebagaimana qiyas, ad-Dali>l itu implisit
didalam nas} itu sendiri. Sebagaimana Ibnu H{azm memberikan penegasan
pada kelompok yang menyamakan ad-Dali>l dengan qiyas, Ibnu H{azm
berkata:
ليل الد و القياسنأخرونأجماع وظن واإلعن النص ايل خروج من لقولنا بالد ن أقوم بجهلهم ظن ٥٧.هم أفحش خطاءا في ظن ئو فأخط، واحد
Artinya: Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendiriankami memegang ad-Dali>l, keluar dari nas} dan ijmak. Dan adalagi orang menyangka bahwa ad-Dali>l dan qiyas itu sama saja,maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatukesalahan yang amat buruk.
Ibnu H{azm membagi ad-Dali>l kepada dua bagian yaitu ad-Dali>l
yang diambil dari nas} dan ad-Dali>l yang diambil dari ijmak. Ad-Dali>l yang
diambil dari nas} terbagi menjadi tujuh yaitu:
a. Nas} yang terdiri dari dua proposisi (muqaddimah), yaitu maqaddimah
qubro dan sughro tanpa konklusi dan natijah, mengeluarkan natijah dari
dari muqaddimah tersebut dinamakan ad-Dali>l. Seperti sabda
Rasulullah “kullu musykiri>n khamrun, wa kullu khamrin hara>mun”, dan
natijah “kullu musykiri>n hara>mun” adalah ad-Dali>l -nya.
b. Nas} menyebutkan syarat yang terkait dengan sifat tertentu. Ketika
syarat itu ada, maka secara otomatis jawaban syarat itu juga ada.
Misalnya firman Allah ‘Azza wa Jalla:
57 Ibnu H{azm, Op.Cit, 2005, h. 714.
34
“Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan
mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu”. (QS.
al-Anfa>l [8]: 38)58
Pada zahir nas} menyebutkan kepada orang-orang kafir yang menentang
Nabi, namun yang diakui keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab
dan penerapan keumuman ini dipahami langsung dari nas}.
c. Nas} memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan
pernyataan lain yang semakna dengan lafaz (al-mutala>’imat). Seperti
firman Allah ‘Azza wa Jalla:
“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang
tua”. (QS. al-‘Ankabu>t [29]: 8)59
Ayat diatas menurut Ibnu H{azm memberikan pelajaran bahwa wajib
berbuat baik pada kedua orang tua dan perbuatan yang bertentangan
dengan itu dilarang termasuk perkataan ah (Uffin).
d. Sesuatu yang tidak ada ketentuan wajib atau haram dari nas} hukumnya
adalah mubah.
e. Proposisi berjenjang (qad}a>ya mudarajat), yaitu pemahaman bahwa
derajat tertinggi dipatikan berada diatas derajat yang lain dibawahnya.
Seperti jika ada pernyataan Abu Bakar lebih baik dari Umar dan Umar
58 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 181.
59 Ibid, h. 397.
35
lebih baik dari Ustman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah
Abu Bakar lebih baik dari Ustman.
f. Kebalikan proposisi (‘aqs qad}a>ya), dimana bentuk proposisi kulliyat
dibalik menjadi proposisi juziyyat. Contohnya, “setiap yang
memabukkan adalah khamar” dibalik menjadi “sebagian dari hal yang
diharamkan adalah yang memabukkan”.
g. Suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa
makna yang secara otomatis menempel padanya (al-makna al-lazim).
Misalnya Zaid sedang menulis, dari pernyataan itu dipahami bahwa
Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan dan bisa digunakannya untuk
menulis.60
Sedangkan ad-Dali>l yang diambil dari Ijmak ada empat macam
yaitu:
a. Ijmak tentang persamaan hukum antara sesama kaum muslimin selama
tidak ada pengkhususan secara ekplisit dalam nas} untuk seseorang
secara tertentu, maka hukum yang tersebut dalam nas} berlaku umum
meskipun lafaznya khusus. Menurut Ibnu H{azm tidak ada perbedaan
dalam hukum qis}as antara orang merdeka membunuh orang merdeka
atau orang merdeka membunuh budak.
b. Ijmak untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu. Artinya ketika
diantara para sahabat mempunyai beberapa versi pendapat dalam suatu
masalah, namun mereka sependapat untuk meninggalkan pendapat
60 Ibnu H{azm, Op.Cit, 2005, h. 714-715.
36
tertentu yang tidak ada dalilnya. Kesepakatan tersebut merupakan ad-
Dali>l akan batalnya pendapat yang ditinggalkan itu. Misalnya, para
sahabat mengatakan bahwa kakek dapat mewarisi bersama saudara laki-
laki, namun mereka berbeda pendapat tentang bagiannya. Kesepakatan
ini merupakan ad-Dali>l kekeliruan pendapat yang mengatakan kakek
sama sekali tidak mendapat warisan.
c. Ad-Dali>l yang didasarkan kesepakatan atas jumlah minimum (aqallu
ma> qi>la), ad-Dali>l ini biasanya berkaitan dengan hukum tentang kadar,
ukuran, jumlah atau hitungan. Misalnya dalam menentukan jumlah
mahar, nafkah, mut’ah istri yang dicerai atau kadar menyapu sebagian
kepala pada saat berwudu. Biasanya dalam hal ini sahabat berbeda
pendapatnya, dalam perbedaan itu jumlah yang terkecil merupakan hal
yang disepakti. Oleh karena itu, jumlah yang terkecillah yang harus
diterima berdasarkan ijmak yang disepakati.
d. Ad-Dali>l istishab, menurut Ibnu H{azm ialah tetapnya hukum yang telah
ditetapkan nas} sampai ada dalil yang mengubahnya. Suatu hukum yang
telah ditetapkan oleh nas} tidak akan berubah disebabkan perubahan
waktu, kondisi dan tempat. Berkaitan dengan ini Ibnu H{azm
memberikan contoh tetap berlanjutnya perkawinan orang yang hilang,
segala tanggungjawabnya atas keluarga dan hak kepemilikannya atas
hartanya masih berlanjut sampai terbukti ia telah meninggal.61
61 Noer Yasin, Op.Cit, h. 56-66.
37
H. Hukum Perkawinan di Indonesia
Hukum perkawinan di Indonesia yang penulis maksud di dalam
penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan
di Indonesia, yang dalam hal ini adalah Buku I Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang mana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 yakni perubahan atas pasal 7 dan adanya penambahan pada pasal 65A,
telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Sedangkan
pasal-pasal yang mengatur tentang perceraian tidak ada perubahan sama
sekali.62
Sebagaimana judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah
tentang hukum saksi dalam talak, maka pembahasannya penulis khususkan
lagi kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perceraian dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa untuk berdirinya hukum perkawinan dalam
bentuk undang-undang tersebut tidaklah mudah dan memakan waktu yang
cukup lama, halangan dan rintangan itu datang dari berbagai kelompok baik
kalangan non muslim karena menganggap tidak sesuai dangan pancasila
maupun dari kalangan muslim itu sendiri karena diantara isi rancangan
62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), h. 2-3.
38
undang-undang yang telah diajukan dianggap tidak sesuai dengan syariat
Islam itu sendiri.63
Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang
masuk dalam panitia kerja maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh
pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam Sidang
Paripurna DPR-RI, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang
tersebut semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga
pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman meberikan kata akhirnya. Pada
hari itu juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah
memakan waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tangga 2 Januari 1974
diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.64
Untuk terlaksananya undang-undang tersebut maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada tahun-tahun
berikutnya ternyata Pengadilan Agama sebagai lembaga yuridis yang
menangani masalah perkawinan antara orang-orang Islam dalam putusannya
banyak yang disparitas dalam menerapkan hukum, oleh karena adanya hal-hal
yang tidak terkover dalam undang-undang perkawinan dan Peraturan
Pemerintah pelaksananya, untuk menangani hal tersebut maka dibuatlah
63 Mohammad Rasjidi, Kasus R.U.U. Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet. Ke-1, h. 22 & 32.
64 Ibid, h. 55.
39
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
pada tanggal 10 Juni, pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
tersebut adalah sebagai acuan baku bagi para Hakim Pengadilan Agama
dalam memutus perkara.65
65 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.Ke-3, h. 26.
40
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SAKSI
A. Talak
1. Pengertian Talak
Istilah cerai atau perceraian dalam bahasa Arab lazim disebut
dengan istilah talak (طالق) . Secara bahasa talak berarti الحل ورفع القید artinya
melepas dan membuka ikatan.66 Talak secara bahasa berasal dari kata -طلق
قاالط-یطلق lafaz dari masdar merupakan talak yang artinya melepaskan atau
menceraikan.67 Dalam pengertian etimologi, kata T{ala>q digunakan untuk
menyatakan melepaskan ikatan secara h}issi>, namun ‘urf mengkhususkan
pengertian T{ala>q itu kepada melepaskan ikatan secara maknawi.
Adapun pengertian talak menurut istilah syarak telah dikemukakan
oleh para ulama fikih, diantaranya yaitu:
Menurut al-Sayyid al-Bakar68 talak adalah:
٦٩.راحالق والفراق والس فظ الآلتي وهي الط كاح بالل عقد الن حل
Artinya: Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz
berikut: at}-T{ala>q, al-Fira>q dan al-Sarra>h.
66 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 PERNIKAHAN, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2019), Cet. Ke-1, h. 359.
67 Mahmud Yunus, Loc. Cit.
68 Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syata (1266-1310H), seorang ulama Syafi’iyyah yang mengarang kitab I’anatu at-Talibin.
69 Al-Sayyid Abu Bakr, I’a>nah at}-T}a>libi>n, (Beirut: Da>r al-Ihya>’ al-Turas| al-‘Arabi>, t.th.),Juz 4, h. 2.
41
Menurut Sayyid Sabiq70 pengertian talak yaitu:
٧١.ةوجي الرابطة الزواج وإنهاء العالقة الز حل
Artinya: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
istri.
Sedangkan menurut Abdurrahma>n al-Jazi>ri>72 talak yaitu:
٧٣كاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.الق إزالة الن الط
Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan
kata-kata tertentu.
Beberapa defenisi diatas menjelaskan bahwa talak adalah
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan
perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, sehingga menurut
Sya>fi>’iyah ditakzir orang orang yang menjimak istrinya sebelum rujuk,
karena tidak boleh rujuk dengan jimak tanpa melafazkan rujuknya terlebih
dahulu. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah
berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya
jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua
menjadi satu dan dari satu menjadi hilang haknya dalam talak raj’i.
70 Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami (1915- 2000 M),seorang ulama mesir yang ahli dibidang fikih.
71 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002), Cet. Ke-1, Julid2, h. 261.
72 Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jaziri (1299-1359H), seorang ulama Mesir yang memiliki keluasan ilmu fikih dan mengarang kitab al-Fiqh ‘Ala>Maza>hib al-Arba’ah.
73 Abdurrahma>n Al-Jazi>ry, Fiqh ‘Ala> al-Maza>hib al-Arba>’ah, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989),Juz 4, h. 278.
42
2. Dasar Hukum Talak
Disyariatkannya talak sebagai solusi ketika dalam suatu rumah
tangga terjadi perselisihan ataupun masalah yang mengharuskan
menggunakan talak sebagai jalan keluar terakhir dalam penyelesaian
masalah tersebut, ini sudah diatur dalam al-Qur’an dan hadis bahkan
secara logika juga bisa diterima.
a. Al-Qur’an
Ada beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang talak
termasuk menjelaskan tatacara menjatuhkan talak yang dianjurkan
dalam syariat Islam, diantaranya yaitu:
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, makahendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktuiddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlahkamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlahmereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakanperbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah makasesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allahmengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At}-T{alaq [65]:1)74
74 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 558.
43
Dalam ayat lain Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
...
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.
(QS. Al-Baqarah [2]: 229)75
b. Hadis
Beberapa hadis dari Rasulullah juga menjelaskan tentang
hukum talak yaitu:
الحالل إلى اهللا عز م قال أبغض ى اهللا عليه وسل صل بي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن الن ٧٦(رواه أبو داود).القالط جل و
“Dari ibnu Umar Rad{iyalla>hu ‘Anhuma> berkata bahwaRasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, perbuatanhalal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak”.(H.R. Abu Daud)
Dalam hadis lain Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda:
وال عتق،نكاحقبلقال طالقالى اهللا عليه و سلمل صخرمة، عن النبي سور بن م الم عن٧٧(رواه ابن ماجة).ملكقبل
“Dari Miswar bin Makhramah, dari Nabi S{alla>llahu ‘Alaihi wa
Sallam beliau bersabda, tidak ada talak sebelum pernikahan,
75 Ibid, h. 36.
76 Abu Daud, Loc.Cit.
77 Ibnu Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,t.th), Juz 1,h. 660. Hasan Shahih menurut al-Albani.
44
dan tidak pemerdekakan budak sebelum kepemilikan”. (H.R.
Ibnu Ma>jah).
Umat Islam sejak masa Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa
Sallam telah berijmak tentang disyariatkannya talak dan logika dasar
manusia bisa menerimanya sebagai salah satu solusi dalam suatu
perkawinan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
3. Rukun dan Syarat Talak
Rukun dan Syarat talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam
talak dan terwujudnya talak bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-
unsur tersebut. Rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut:
a. Suami
Suami adalah orang yang berhak menjatuhkan talak. Oleh
karena talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak
tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan
yang sah, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Ma>jah yang telah
disebutkan sebelumnya.
Untuk sahnya suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:
1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang
dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak
akalnya karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang
akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf
otaknya.
45
2) Balig, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang
yang belum dewasa. Hukum Islam memungkinkan terjadinya
perkawinan bagi anak dibawah umur yang dalam akad nikah
dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak
menikahkan anak dibawah umur perwaliannya itu tidak
dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah
dinikahkannya.
3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksudkan dengan atas kemauan
sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk
menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan
karena dipaksa oleh orang lain.78
b. Isteri
Perempuan yang ditalak harus berada di bawah wilayah atau
kekuasaan laki-laki yang menjatuhkan talak yaitu istri yang masih
terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang
sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj’i dan masih berada dalam
masa iddah, karena seorang perempuan pada masa iddahnya masih
berstatus sebagi istri yang memiliki hak dan kewajiban dengan
suaminya.79
Sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya:
نكاحقبلقال طال
78 Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit, h. 202.
79 Amir Syarifuddin, Op.Cit, 2011, h. 207.
46
“Tidak ada talak sebelum pernikahan”.
Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai
berikut:
1) Istri itu masih tetap berada dalam wilayah keuasaan suami dan
istri yang sedang menjalani masa iddah.
2) Istri tersebut harus berdasarkan akad perkawinan yang sah, jika ia
menjadi istri dengan akad nikah yang batil seperti memadu dua
orang perempuan bersaudara maka talak yang demikian tidak
dipandang ada.
c. S}igat Talak
S}igat talak adalah kata-kata yang diucapakan oleh suami
terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik sarih maupun kinayah,
baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara
ataupun dengan suruhan orang lain.80
Jumhur fuqaha>’ berpendapat bahwa talak terjadi bila suami
yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu
yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh
karena itu kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan
tetapi belum mengucapkan apa-apa maka belum terjadi talak.81
80 Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit, h. 204.
81 Amir Syarifuddin, Op.Cit, 2011, h. 208.
47
Ulama Ahlu Sunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya
talak sebagaimana disebutkan diatas, yang berbeda dari golongan ini
adalah golongan ulama Syi>’ah Ima>miyyah, bagi mereka ada rukun yang
keempat yaitu kehadiran saksi. Saksi itu harus hadir dan menyaksikan saat
mengucapkan talak, bila tidak dihadiri saksi, talak tersebut dinyatakan
belum terlaksana. Demikian juga pandangan dari ulama az}-Z{ahiri
termasuk Ibnu H{azm yang mewajibkan saksi dalam talak, namun
mejadikannya sebagai syarat sah bukan rukun.82
4. Macam-Macam Talak
a. Talak Menurut Prosedurnya
Secara prosedural talak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu
talak sunni karena sesuai dengan sunah Nabi atau syariat Islam dan
talak bid’i atau bid’ah karena tidak sesuai dengan sunah atau syariat
Islam.
1) Talak Sunni
Talak sunni yaitu talak yang pelaksaannya sesuai dengan
sunah dan petunjuk agama. Bentuk talak sunni yang disepakati
oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana
istri pada waktu itu tidak dalak keadaan haid atau pada masa suci
yang belum pernah digauli oleh suaminya, dengan tujuan setelah
talak dijatuhkan istri dapat segera menjalankan iddahnya. Hal ini
sesuai dengan firman Allah ‘Azza wa Jalla:
82 Ibid, h. 214.
48
...
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah
waktu iddah itu ...”. (QS. At}-T}alaq [65]: 1)83
2) Talak Bid’i
Talak bid’i yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut
ketentuan syariat, bentuk talak yang disepakati ulama yang
termasuk dalam kategori talak bid’i ialah talak yang dijatuhkan
sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun
telah digauli oleh suami.
Yusuf Qarad}awi mengatakan bahwa hukum mentalak istri
yang dalam keadaan haid adalah haram sebagaimana diharamkan
pula menceraikannya pada waktu suci yang telah melakukan
hubungan intim dengannya, karena siapa tahu spermatozoanya
melekat pada rahim istrinya dalam persetubuhan kali ini.84
83 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 558.
84 Yu>suf Qarad}awi, Halal dan Haram dalam Islam, penj. Abu Sa’id al-Falahi dan AunurRafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 242.
49
Hukum talak bid’i juga diharamkan karena memberi
mudarat kepada istri, yaitu memperpanjang masa iddahnya.
Sebagaimana Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
رسول عهدعلى،ق امرأته وهي حائضه طل عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن م عن ى اهللا عليه وسل اب رسول اهللا صل فسأل عمر بن الخط ،مى اهللا عليه وسل اهللا صل
ثم ،ى تطهرليمسكها حت جعها ثم امره فلير مى اهللا عليه وسل ذلك فقال رسول اهللا صل ة فتلك العد ،ق قبل أن يمس وإن شاء طل ،إن شاء أمسك بعدتطهر ثم تحيض ثم
٨٥)رواه البخاري(ساءق لها الن طل يتي أمر اهللا أن ال
“Dari Ibnu Umar Rad{iyalla>hu ‘Anhuma>, sesungguhnya iamenjatuhkan talak isterinya, yang mana isterinya ituberada dalam keadaan haid, pada masa RasulullahS{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam kemudian Umar berkata, akumenanyakan kepada Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi waSallam tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: suruhia untuk merujukinya, kemudian hendaklah iamemegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudiansuci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelumdisetubuhi. Itulah iddah yang telah ditetapkan Allah untukmenjatuhkan talak para wanita”. (H.R. Bukha>ri)
Walaupun ulama sepakat tentang haramnya mentalak istri
yang sedang haid, namun mereka berbeda pendapat apakah talak
tersebut jatuh atau tidak. Jumhur fuqaha>’ berpendapat bahwa
talak yang dijatuhkan pada masa istri haid tersebut jatuh, alasanya
adalah hadits tersebut diatas dinyatakan bahwa Ibnu Umar yang
menceraikan istrinya dalam haid tersebut disuruh rujuk kepada
85 Al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Bukha>ri>, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), Juz 5, h. 199.
50
istrinya, rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah
terjadi talak.86
Sebagian ulama termasuk Ibnu H{azm berpendapat bahwa
talak dalam masa haid itu tidak jatuh.87 Karena talak seperti itu
tidak sesuai dengan sunah dan termasuk kedalam perbuatan
bid’ah, sebagaimana sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah
S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam :
ليس عليه أخبرتني عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من عمل عمال٨٨.أمرنا فهو رد
“’Aisyah Rad}iyallahu ‘Anha memberitahuku bahwaRasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:Barangsiapa mengamalkan sesuatu amalan yang tidaksesuai dengan perintah kami, maka ia ditolak”. (HR.Muslim)
b. Talak Menurut Kebolehannya untuk Rujuk Kembali
1) Talak Raj’i
Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang
suami kepada istrinya, namun suami masih mempunyai hak untuk
rujuk dan kembali kepada istrinya selama masih dalam masa
iddahnya. Kesempatan untuk kembali rujuk bagi seorang suami
hanya dua kali, sebagaimana Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
86 Amir Syarifuddin, Op.Cit, 2011, h. 219.
87 Ibnu H{azm, Op.Cit, t.th, Juz 9. h. 363.
88 Muslim, Shahih Muslim, (Riyad: Da>r at-Tayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi>’, 2006),Cet. Ke-1, Julid 1, h. 822.
51
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah [2]: 229)89
2) Talak Ba’in
Talak ba’in adalah talak yang putus secara penuh dalam
arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali
dengan pernikahan yang baru, talak ba’in inilah yang tepat
disebut dengan putusnya perkawinan. Talak ba’in terbagi dua
yaitu:
Pertama, talak bain sugra, adalah talak yang suami tidak
boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi
dengan pernikahan yang baru tanpa adanya muh}allil, yang
termasuk talak bain sugra adalah talak satu atau dua yang telah
habis masa iddahnya, talak yang dilakukan kepada istri yang
belum pernah digauli sekalipun, talak karena khulu’ dan
perceraian akibat fasakh.
Kedua, talak bain kubra, yaitu talak suami yang tidak
mungkin suami rujuk kepada mantan istrinya. Jika ingin kembali
kepada istrinya, maka istri tersebut harus terlebih dahulu menikah
dengan lelaki lain dan lelaki tersebut menceraikannya setelah
89 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 36.
52
digaulinya dan habis masa iddahnya, yang termasuk talak ba’in
kubra adalah istri yang telak ditalak tiga dan percerain yang
terjadi karena li’an.90
c. Talak Menurut Jenis Lafaznya
1) Talak dengan Lafaz S}arih
Talak s}arih yaitu talak dengan menggunakan kata-kata
yang jelas dan tegas, dapat langsung dipahami sebagai pernyataan
talak seketika diucapakan dan tidak perlu kepada niat. Seperti
dengan mengucapkan “Aku Cerai” atau “Kamu telah aku cerai”.
Menurut Imam Sya>fi’i> dan orang-orang yang sepakat
dengannya kata-kata yang bisa dipergunakan untuk talak s}arih
ada tiga, yaitu t}ala>k, fira>q (pisah) dan sarra>h (lepas) dan bahasa
lain yang semakna dengan tiga kata tersebut, karena ketiga kata
tersebut telah dipergunakan didalam al-Qur’an dan hadis yang
menunjukkan makna perceraian.91
2) Talak dengan Lafaz Kinayah
Talak kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata
sindiran atau samar-samar dan perlu adanya niat dari suami untuk
jatuhnya talak, karena kata-kata yang diucapkan tidak
menunjukkan pengertian talak secara langsung. Seperti ucapan
90 Amir Syarifuddin, Op.Cit, 2011, h. 225.
91 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, penj. HaritsFadly, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 350.
53
“selesaikan sendiri segala urusanmu” atau “pulanglah kepada
keluargamu”, ucapan seperti ini mengandung kemungkinan cerai
dan mengandung kemungkinan yang lain.92
Talak dengan menggunakan lafaz kinayah tergantung niat
atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bila kebiasaannya lafaz
itu yang digunakan untuk menceraikan istri maka jatuhlah
talaknya, jika tidak maka tidak jatuh. Begitu juga dengan niat,
apabila saat mengucapkan talak suami meniatkan talak maka
jatuh talaknya, jika tidak maka tidak jatuh talaknya.
d. Talak Menurut Mulai Berlakunya
1) Talak Munjaz
Talak munjaz adalah talak yang keluar dengan s}igat
mutlak dan tidak disandarkan kepada masa depan atau sesuatu
yang akan terjadi dimasa mendatang, seperti ucapan suami “kamu
saya ceraikan”. Hukum talak munjaz jatuh secara langsung ketika
talak itu dikeluarkan, syaratnya suami yang mengeluarkan talak
itu layak untuk menjatuhkannya sementara istri pun pantas
dijatuhi talak.93
92 Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit, h. 196.
93 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Op.Cit, h. 398.
54
2) Talak Mu’allaq
Talak mu’allaq adalah talak yang digantungkan pada
suatu perbuatan atau kejadian yang akan terjadi, bisa saja
dikaitkan dengan perbuatan istri, suami atau sesuatu kejadian
yang lain.94 Jika digantungkan kepada sesuatu yang sudah pasti
terjadi seperti datangnya malam atau siang, terbitnya matahari
atau bulan dan sebagainya, maka talaknya jatuh pada saat itu juga
sebelum syarat itu terpenuhi.95
Talak mu’allaq berbeda dengan taklik talak yang berlaku
dibeberapa tempat termasuk di Indonesia yang diucapkan oleh
suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik talak adalah
sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya
disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika
suami tidak memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu
dapat mengajukan kepengadilan sebagai alasan untuk
perceraian.96
3) Talak Mud}a>f Li al-Mustaqba>l
Talak ini maksudnya akan berlaku pada waktu yang telah
ditetapkan dengan hitungan waktu tertentu, seperti hitungan jam,
hari, minggu, bulan atau tahun. Misalnya seorang suami berkata
94 Ahmad Sarwat, Op.Cit, h. 392.
95 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Penj. Abdul Gofar EM, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1, h. 300.
96 Amir Syarifuddin, Op.Cit, 2011, h. 226.
55
“kamu aku ceraikan sebulan lagi”, maka ketika jatuh tempo
istrinya tersebut akan tertalak.97
Berkenaan dengan rukun dan syarat serta pembagian dan macam-
macam talak pada umumnya Ibnu Hazm hampir sama dengan jumhur
fuqaha’, hanya saja sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada BAB I,
Ibnu Hazm menambahkan kehadiran dua orang saksi yang adil sebagai syarat
sahnya talak.
B. Saksi
1. Pengertian Saksi
Dalam bahasa arab saksi disebut شاھد yang berbentuk isim fa’il.
Kata tersebut berasal dari masdar /شھادة شھود akar katanya adalah - شھد
شھود - یشھد yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan
(dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui,
bersumpah, mengetahui dan menjadikan sebagai saksi.98
Sedangkan pengertian saksi menurut istilah adalah orang yang
mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena
dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.99
Dalam buku-buku fikih agak sulit ditemukan adanya pengertian
saksi menurut istilah syarak, pada umunya yang ditemukan adalah
97 Ahmad Sarwat, Loc.Cit.
98 Mahmud Yunus, Op.Cit, h. 207.
99 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit. h. 107.
56
pengertian kesaksian (الشھادة). Adapun pengertian kesaksian menurut
ulama fikih yaitu:
Salam Madkur mengartikan kesaksian sebagai berikut:
١٠٠.هادة إلثبات حق على الغيرهادة عبارة عن إخبار صدق في مجلس الحكم بلفظ الش الش
“Kesaksian adalah istilah pemberitahuan sesorang yang benar
didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan
hak orang lain.”
Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa saksi menurut
istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan
memepertanggungjawabkan secara apa adanya.
2. Dasar Hukum Saksi
a. Al-Qur’an
Adapun yang menjadi dasar hukum tentang persaksian
diantaranya adalah firman Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la :
... ...
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah”. (QS. at}-T{ala>q [65]: 2)101
Dalam ayat lain Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la berfirman:
100 Ibid, h. 106.
101 Departeman Agama RI, Op.Cit, h. 558.
57
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yangbenar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allahbiarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaumkerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahukemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsukarena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamumemutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, makasesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yangkamu kerjakan”. (QS. an-Nisa>’ [4]: 135)102
b. Hadis
Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
، هداءكم بخير الش بر لم قال أال أخأن النبي صلى اهللا عليه و سابن خالد الجهنييد عن ز ١٠٣قبل أن يسألها. (رواه مسلم)تههادالذي يأتي بالش
“Dari Zaid bin Kha>lid al-Juhni Rad{iyalla>hu ‘Anhu,bahwasanya Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:bukankah sudah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baiknya saksi?, ialah orang yang memberikan kesaksiannyasebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. (HR. Muslim)
Dalam hadis lain Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda:
102 Ibid, h. 100.
103 Muslim, Loc.Cit.
58
قال رسول اهللا صلى اهللا يز، عن سليمان بن موسى بإسناده قال:أخبرنا سعيد بن عبد العز .ذي غمر على أخيهزان وال زانية، وال وال ،عليه و سلم ال تجوز شهادة خائن وال خائنة
١٠٤(رواه أبو داود)
“Telah menceritakan kepada kami Said bin Abdul ‘Azi>z dariSulaima>n bin Musa> dengan sanadnya, ia berkata RasulullahS{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Tidak diperbolehkankesaksian seorang laki-laki dan wanita yang berkhianat, dantidak pula laki-laki serta wanita pezina dan orang yangmemiliki kedengkian terhadap saudaranya”. (HR. Abu Daud)
3. Syarat-Syarat Saksi
Untuk diterimanya kesaksian seseorang menjadi saksi, maka harus
memenuhi beberapa syarat, yang terbagi kepada syarat dasar dan syarat
teknis, yang termasuk syarat- syarat dasar yaitu:
a. Beragama Islam
Empat mazhab fikih yang masyhur sepakat mengatakan bahwa
syarat yang paling utama dari saksi adalah Islam karena firman Allah
Subh}a>nahu wa Ta’a>la “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil”, dan makna adil disini dipahami dengan ‘ada>latud-di>n (0rang
yang beragama Islam), dan telah menjadi ijmak dikalangan mazhab
Sya>fi’i> bahwa orang pernah melakukan dosa kesaksiannya tetap dapat
diterima, namun orang kafir tetap tidak diterima kesaksiannya.105
104 Abu Daud, Sunan Abi> Da>ud, Op.Cit, Ju 3, h. 299. Hasan menurut Al-Alba>ni.
105 Ahmad Sarwat, Op.Cit. h. 123.
59
b. Taklif
Syarat yang kedua dari saksi adalah taklif, artinya seorang saksi
itu harus seorang mukalaf, yaitu akil (berakal) dan balig. Telah menjadi
ijmak dikalangan jumhur fuqaha>’ bahwa orang gila tidak pernah bisa
diterima kesaksiannya dan akal sehat pun tidak akan dapat menerima
kesaksian orang gila.106
Jumhur fuqaha>’ juga sepakat bahwa syarat saksi haruslah
seorang yang sudah balig, berdasarkan firman Allah ‘Azza wa Jalla,
.. ..
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu).” (QS. al-Baqarah [2]: 282)107
Dalam ayat ini Allah ‘Azza wa Jalla menggunakan istilah rijal,
yang maknanya bukan hanya sekedar bejenis kelamin laki-laki, tetapi
yang lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau
minimal sudah balig.108
c. Al-‘Ada>lah
Al-‘Ada>lah dalam bahasa Arab dan istilah fikih sangat jauh
berbeda dengan makna kata adil atau keadilan didalam istilah bahasa
Indonesia. Al-‘Ada>lah dalam bahsa Arab sering disebut sebagai
106 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, h. 112.
107 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 48.
108 Ahmad Sarwad, Op.Cit, h. 124.
60
ungkapan atas suatu perkara yang seimbang diantara berlebihan dan
kekurangan, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat
Al-‘Ada>lah adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan
dengan terang-terangan.109
d. Laki-laki
Mazhab Ma>liki, Sya>fi’i> dan Hanbali sepakat mengatakan bahwa
syarat saksi dalam pernikahan adalah keduanya laki-laki. Maka
kesaksian wanita dalam pernikahan termasuk juga dalam talak tidak sah
walaupun wanita tersebut dua orang. Abu Ubaid meriwayatkan dari az-
Zuhri berkata,
Telah menjadi Sunah Rasulullah S{alla>llahu ‘Alaihi wa Sallam
bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita adalam masalah
hudud, nikah dan talak.
Namun mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika jumlah wanita
tersebut dua orang maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki,
sebagaimana firman Allah Subh}a>nahu wa Ta’a>la,
.. ..
“Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan”. (QS. al-Baqarah [2]: 282)110
109 Ibid., h. 126.
110 Departemen Agama RI, Loc.Cit.
61
Sedangkan Ibnu H{azm berpendapat bahwa kedudukan
perempuan dan laki-laki dari segi keadilannya adalah sama, hanya saja
kekuatan kesaksian seorang perempuan adalah setengah dari laki-laki.
Ibnu H{azm mengatakan bahwa dalam perkara nikah, talak, rujuk, serta
harta benda saksinya adalah dua orang laki-laki muslim yang adil atau
satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau dengan empat orang
wanita itu sama saja.111
e. Merdeka
Seorang hamba sahaya atau budak tidak sah bila menjadi saksi
sebuah pernikahan, talak dan rujuk. Sebab seorang hamba sahaya atau
budak bukanlah orang yang mempunyai hak dalam sebuah persaksian
ataupun dalam sebuah pengadilan, juga karena orang merdeka kata-
katanya berlaku terhadap orang lain yang dengan demikian merupakan
kekuasaan (wilayah), sedangkan hamba sahaya tidak berhak terhadap
kekuasaan (wilayah) itu.112
Adapun syarat-syarat teknis dalam persaksian adalah sebagai
berikut:
a. Sehat pendengarannya
b. Sehat penglihatannya
c. Mampu berbicara
111 Ibnu H{azm, Op.Cit, t.th, Juz 9, h. 396.
112 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muh}ammad al-Husaini, Kifa>yatu al-Akhya>r fi> H{illi Ga>yahal-Ikhtis}ar, (t.tp: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), h. 276.
62
d. Sadar atau terjaga ketika menyaksikan perkara
e. Memahami bahasa orang yang disaksikan
f. Bukan anak dari para pihak.113
113 Ahmad Sarwad, Op.Cit, h. 130-132.
90
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah
dilakukan dengan uraian yang telah terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Ibnu H{azm berpendapat bahwa menghadirkan saksi dalam talak
merupakan kewajiban bagi suami, sehingga tidak sah talak yang tidak
disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hukum perkawinan di
Indonesia juga mewajibkan saksi dalam talak, dan pelaksaannya harus di
depan sidang Pengadilan Agama, maka talak yang dilakukan diluar sidang
Pengadilan Agama dianggap talak liar dan dinyatakan tidak sah.
2. Walaupun pendapat Ibnu H{azm dan hukum perkawinan di Indonesia
sama-sama mewajibkan saksi dalam talak, namun keduanya tidak relevan,
karena menurut hukum perkawinan di Indonesia talak harus dihadapan
sidang Pengadilan Agama sedangkan menurut Ibnu H{azm talak tidak
harus di depan persidangan. Tidak bisa dikatakan relevan juga karena
undang-undang yang mengatur tentang perceraian di Indonesia tidak
menyebutkan secara jelas siapa dan berapa jumlah saksi dalam ikrar talak
tersebut.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan,
penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
91
1. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, oleh karena
itu hendaknya tiap-tiap orang menghindari terjadinya perceraian dalam
rumah tangga.
2. Hendaknya para ahli hukum Islam di Indonesia kembali mengkaji defenisi
talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agar tidak menimbulkan
dualisme pemahaman hukum ditengah masyarakat. Talak yang terjadi
diluar Pengadilan Agama hendaknya tetap diakui, sehingga Pengadilan
Agama tidak hanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai di
Pengadilan, tetapi juga berperan sebagai tempat untuk melegalisasi talak
yang sudah terjadi diluar sidang Pengadilan Agama.
3. Hendaknya pemerintah tidak hanya mengupayakan cara mempersulit
terjadinya perceraian melalui hukum saja, tetapi juga mengoptimalkan
fungsi Pengadilan Agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang dampak dari perceraian, agar masing-masing individu benar-benar
memahami konsep talak secara mendalam sehingga seseorang tidak
semena-semena menjatuhkan talak dalam rumah tangga.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Penj.Harits Fadly, Surakarta: Era Intermedia.
Abdul Rahman Ghazaly, 2006, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana.
Abdurrahma>n Al-Jaziri>, 1989, Fiqh ‘Ala> al-Maza>hib al-Arba>’ah, Beirut: Da>r al-Fikr.
Abu Da>ud, 1994, Sunan Abi> Da>ud, Beirut: Da>r al-Fikr.
Abu> Zahrah, 1957, al-Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah, t.tp: Da>r al-Fikr al-Arabi>.
Ahmad Sarwat, 2019, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 PERNIKAHAN, Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama.
Ahsin W. Al-hafidz, 2013, Kamus Fiqh, Jakarta: Amzah.
Al-Bukha>ri, 1994, Shahi>h Bukha>ri, Beirut: Da>r al-Fikr.
Al-Sayyid Abi> Bakr, t.th, I’a>nah at}-T}alibi>n, Beirut: Da>r al-Ihya>’ al-Turas| al-‘Arabi>.
Amir Syarifuddin, 2005, Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum IslamKontemporer di Indonesia, Jakarta: PT Ciputat Press.
, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
An-Nawawi, 2011, Syarah Shahih Muslim, Penj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.
Departemen Agama R.I., 1999, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral PembinaanKelembagaan Agama Islam.
Faruq Abdul Mu’t}i, 1992, Ibnu H{azm Az}-Z{ahiri, Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ibnu H{azm, 2005, Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l Al-Ah}ka>m, Kairo: Da>r al-Hadis|.
, t.th, Al-Muh}alla> Bi al-As|ar, Beirut: Da>r al-Fikr.
Ibnu Kas|ir, 1992, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}im, Beirut: Maktabah an-Nu>r al-‘Ilmiyah.
Ibnu Ma>jah, t.th, Sunan Ibnu Ma>jah, Beirut: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Ibnu Taimiyah, 1998, Naqdu Maratib al-Ijma’, Beirut: Dar Ibnu Hazm.
, 2004, Majmu>’ Fata>wa>, Madinah: Mujamma’i al-Ma>liki Fahad li T{iba>’atial-Mushhafi al-Syari>fi.
J. Supranto, 1997, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Jakarta: PT RinekaCipta.
Koto, Alaidin, 2014, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers.
M Ali Hasan, 1996, Perbandinagn Mazhab, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mahi M. Hikmat, 2014, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi danSastra, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mahmud Yunus, 2010, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Mahmud Yunus waDzurriyah.
Mohammad Rasjidi, 1974, Kasus R.U.U. Perkawinan dalam Hubungan Islam danKristen, Jakarta: Bulan Bintang.
Muhammad bin Ali asy-Syaukani, 2006, Nailu al-Autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, t.tp: Dar Ibnu al-Jauzyah.
Muh}ammad Abu> Zahrah, t.th, Tarekh al-Maza>hib al-Isla>miyah, Kairo: Da>r al-Fikral-Arabi>.
Muh}ammad bin Idri>s Asy-Sya>fi’i>, 2001, Al-Umm, t.tp: Da>r al-Wafa’.
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Semarang:Pustaka Rizki Putra.
Muslim, 2006, Shahih Muslim, Riyad: Da>r at-Tayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzi>’.
Mustafa Sa’id al-Kha>n, 1982, As|ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>’id al-Us}uliyyah fi> Ikhtila>fal-Fuqaha>’, Beiru: Muassasah ar-Risa>lah.
Noer Yasin, 2012, Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani,Malang: UIN Maliki Press.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Publishing.
Qardhawy, Yusuf, 2000, Halal dan Haram dalam Islam, Penj. Abu Sa’id al-Falahidan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press.
Republik Indonesia, 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Jakarta: Laksana.
Republik Indonesia, 2013, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, Jakarta: Laksana.
Rofiq, Ahmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sayyid Sabiq, 2002, Fiqh as-Sunnah, Beirut: Muassasah ar-Risa>lah.
Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung:Alfabeta.
Syaikh Ahmad Farid, 2007, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Syaikh Hasan Ayyub, 2001, Fikih Keluarga, Penj. Abdul Gofar EM, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.
Taqiyyuddin Abu> Bakar bin Muh}ammad al-Husaini, t.th, Kifayatu al-Akhya>r fi>Halli Gha>yah al-Ikhtis}a>r, t.tp: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Jurnal:
A. Halil Thahir, Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushulal-Ahkam, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016.
Ahmad Tajuddin Arafat, Filsafat Moral Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa as-Siyar Fi Mudawati an-Nufus, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni 2013.
M. Lathoif Ghozali, Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam FiUshul Al-Ahkam, Jurnal hukum Islam, Vol. 01. No. 01 Maret 2009.
Muh Said HM, Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm Tentang Kesejahteraan TenagaKerja, Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah. Vol 3, No. 2,Desember 2016.
Zuhri, Ibnu Hazm al-Andalusi dan Khilafah, Esensia. Vol 17, No. 2, Oktober 2016.
Internet & PDF
https://www.pamataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=431:ikrar-talak-harus-di-depan-sidangpengadilan&catid=37:artikel&Itemid=87.
Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999, Perlembagaan NegaraBrunei Darussalam.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI.
RIWAYAT HIDUP
Joshua Suherman, lahir di Tandai Kec. Sangir Kab.
Solok Selatan Prov. Sumatera Barat pada tanggal 07
September 1996, merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara, dilahirkan dari pasangan Bapak Yasriman dan
Ibu Yarnida. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD
Negeri 23 Tandai pada tahun 2009, lalu melanjutkan ke
MTsS PP Bustanul Huda Malus hingga tahun 2012. Pada
tahun 2015 penulis tamat dari MAS PP Bustanul Huda
Malus dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan
Hukum Keluarga Program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
Selama menjalani proses perkuliahan penulis tinggal di Ma’had al-Jami’ah
atau Asrama Putra UIN SUSKA Riau dari semester I-IV dan pada semester V atau
pada semester ganjil tahun ajaran 2017-2018 penulis terpilih sebagai mahasiswa
Student Exchange ke Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei
Darussalam. Setelah program Student Exchange berakhir penulis langsung
kembali ke tanah air pada awal perkuliahan semester VI dan langsung mengikuti
Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Muara Labuh Kab. Solok
Selatan selama dua bulan. Kemudian pada semester VII penulis kembali aktif di
Ma’had al-Jami’ah UIN SUSKA Riau sebagai Musyrif di Wihdah Abu Bakar.
Penulis juga aktif pada salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu Forum Kajian
Mahasiswa Syariah dan Hukum (FK-MASSYA) dan diamanahkan menjadi ketua
umum periode 2018.
Akhirnya, untuk memenuhi tanggungjawab terakhir sebagai mahasiswa
program S1, penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “RELEVANSI
PENDAPAT IBNU HAZM DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA TENTANG SAKSI DALAM TALAK”, yang di Munaqasyahkan
pada tanggal 06 November 2019, alhamdulilah lulus dengan predikat sangat
memuaskan, sehingga penulis resmi bergelas Sarjana Hukum (SH).