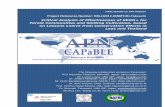REDD Antitesis Reboisasi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of REDD Antitesis Reboisasi
REDD:Antitesis Reboisasi?
Tim Penulis : Muhammad AnsorNurul QomarSuryadiHelmiHusni ThamrinTaufik QurachmanJomi SuhendriRifai LubisEdi IndrizalAndiko
Tim Editor : Ahmad ZazaliHarry OktavianMu’ammar Hamidy
Design Cover : Mamay
Diterbitkan Oleh : Scale Up - Sustainable Social Development Partnership(Isi diluar tanggungjawab percetakan)
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
v
Kata Pengantar
Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia menjadi isuyang sangat penting di tengah perdebatan mencari formatpengurangan pemanasan global, jika di tingkat global
menyumbang 20 % dari total emisi, maka di Indonesia deforestasidan degradasi menyumbang sebesar 80% dari total sumber emisisecara nasional.
Sebenarnya pemerintah sudah mengklaim telah banyakmelakukan berbagai program di masa lalu hingga sekarang untukmengatasi deforestasi dan degradasi hutan, sebut saja melaluiprogram reboisasi, GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan), dan terakhir ini ada Gerakan Indonesia Menanam SejutaPohon dengan slogan “one man one tree.” Namun secara bersamaanPemerintah juga banyak mengeluarkan perizinan konsesi untukberbagai perusahaan yang mengkonversi hutan alam menjadiperkebunan sawit maupun akasia. Sehingga masih cukup susahbagi kita untuk mengukur apa dampak dari program rebosisasi,GNRHL, dan Gerakan Indonesia Menanam yang dicanangkanpemerintah tersebut.
Situasi Indonesia saat ini menunjukkan lemahnya dukunganpolitik dan hukum untuk isu penyelamatan sumber daya alam darieksploitasi yang merusak dan mengabaikan nasib masyarakat adat/asli dan lokal sekitar dan di dalam hutan yang memiliki
vi
ketergantungan langsung dan tidak langsung terhadap hutan.Lemahnya dukungan politik dan hukum ini setidaknya terlihatbanyaknya izin-izin eksploitasi hutan yang dikeluarkan baik olehpemerintah daerah maupun pemerintah nasional.
Niat untuk memperbaiki praktik pengelolaan hutan yang propenyelamatan ekologi dan pro penyelamatan sumber-sumberkehidupan jangka panjang seringkali kali kalah ketika berbenturandengan agenda pemerintah untuk meningkatan investasi danpendapatan daerah dan negara, serta alasan bahwa Indonesia saatini sedang membangun atau berkembang jadi mutlak memerlukanpembukaan hutan untuk memicu pertumbuhan agroindustri, tanpatahu secara pasti kapan pembangunan yang mengeksploitasi sumberdaya alam ini harus diakhiri.
Namun dengan munculnya komitmen Presiden RI untukmenerapkan moratorium perizinan pembukaan hutan mulai awaltahun 2011, maka sekali lagi kita patut untuk selalu mengingatkanpemerintah untuk membuktikan realisasinya. Letter of Intent (LoI)atau surat yang menyatakan kesamaan niat antara Indonesia denganNorwegia, dan komitmen Presiden RI menurunkan emisi 26 %secara mandiri dan bisa hingga 41 % apabila ada bantuan luar negerihingga tahun 2020 adalah sederetan kebijakan politik yang belumditindaklanjuti dengan kebijakan hukum yang memadai hingga saatini. Begitu juga terhadap banyaknya gagasan proyek demonstrasiREDD/REDD+ seperti di ekosistem Ulu Masen Aceh, Papua,Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Semua itu seyogyanya harus disertai dengan payung hukum yangmemadai untuk menjamin bahwa hutan bukan hanya dijadikan objekdagangan karbon semata-mata dan mengesampingkan hak-hakmasyarakat adat/asli dan lokal, tapi adalah upaya sadar yangterintegrasi secara nasional yang berimbas pada reformasipembangunan di semua sektor ke arah yang pro penyelamatanekologi dan pro penyelamatan sumber-sumber kehidupan jangkapanjang. Amin. Semoga ini bisa menjadi kenyataan.
vii
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanpeneliti yang telah merampungkan penyusunan buku ini antara lainHary Oktavian selaku Koordinator Program Scale Up, Andiko dariHuMA yang memberi nasehat dari awal hingga buku ini siap dicetak,Jomi Suhendri dari Qbar Sumatera Barat, M. Ansor, Suryadi dariLBH Pekanbaru, Nurul Qomar dari Program studi KehutananUniversitas Riau,dan Helmi dari PSHK ODA di Jambi. Semogabuku ini berguna!
Ahmad ZazaliDirektur Eksekutif Scale Up
Daftar Isi
Kata Pengantar ..................................................................................... vDaftar Isi ............................................................................................... ixDaftar Tabel, Grafik, dan Box ........................................................ xiiiDaftar Wawancara .............................................................................. xv
Bagian PertamaPendahuluanLatar Belakang .................................................................................... 03
Bagian KeduaSenarai Pengaturan Penghutanan Kembali dalamPolitik Kebijakan Kehutanan1. Konsep Penguasaan Sumber Daya Alam ................................. 192. Kebijakan Umum Pengelolaan Hutan ...................................... 213. Konsep dan Sejarah Konservasi ................................................ 234. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan .................. 28
1) Kondisi Hutan dan Lahan saat Pencanangan GN-RHL . 282) Kelembagaan GN-RHL ........................................................ 323) Perencanaan GN-RHL .......................................................... 36
A. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan .......... 36B. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
5 Tahunan .......................................................................... 37
ix
x
C. Rencana Teknis Tahunan (RTT) .................................... 39D. Rencana Teknis Kegiatan ................................................ 39
4) Waktu dan Tahapan Penyusunan Rancangan .................... 405) Pelaksanaan GN-RHL ........................................................... 406) Target RHL pada GN-RHL ................................................. 44
5. Politik Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia
Bagian KetigaKebijakan Penghutanan dan Implementasinyadi Tiga Lokasi di Tiga Propinsi di Sumatera3.1. Kontestasi Arus Deforestasi dan Reforestasi:
Studi Kasus Politik Hukum PengelolaanKawasan Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling,Propinsi Riau .............................................................................. 57
3.1.1. Kebijakan Di Bidang Kehutanan Propinsi Di Riau .......... 571. Potret Deforestasi dan Degradasi Hutan Riau ............... 572. Kebijakan-Kebijakan Perlindungan Hutan ...................... 603. Suaka Margasatwa Rimbang Baling .................................. 624. Land Use dan Ancaman Ekosistem SM
Rimbang Baling .................................................................... 65
3.1.2. Review Kondisi Sosial Ekonomi dan Budayadi Rimbang Baling ..................................................................... 741. Kampung-kampung di Rimbang Baling .......................... 742. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi ............................... 793. Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Alam . 84
A. Siklus Pertanian dan Peladangan ................................. 85B. Lubuk Larangan di Rimbang Baling ........................... 88
3.1.3. Studi Kasus Implementasi Rehabilitasi Hutandi Rimbang Baling ..................................................................... 961. Brief Review Kebijakan Rehabilitasi
xi
Hutan dan Lahan .................................................................. 962. Kebijakan Rehabilitasi Hutan di Riau .............................. 983. Potret Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan di Rimbang Baling ................................................. 102A. Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu .......... 104B. Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi ..... 108
4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilandan Kegagalan .................................................................... 110
3.2. Studi Politik Hukum Perlindungan Hutandari Reforestasi : Menyigi Kebijakan RehabilitasiHutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat .................... 113
3.2.1. Kebijakan Kehutanan dan GN-RHL di Sumatera Barat 1131. Kondisi Kehutanan dan Kebijakan Kehutanan
di Sumatera Barat ............................................................... 1132. Target RHL dalam GN-RHL di Sumatera Barat ......... 115
3.2.2. Potret Pelaksanaan GN-RHL di Nagari AmpaluKabupaten Lima Puluh Kota ................................................. 1191. Gambaran Umum Lokasi dan Masyarakat
Nagari Ampalu ................................................................... 1192. Pelaksanaan GN-RHL dan Permasalahannya
di Nagari Ampalu ............................................................... 1233. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan
di Nagari Ampalu ............................................................... 126
3.3. Pelestarian Fungsi Kawasan Hutan melalui REDD ? :Studi Kasus di Taman Nasional Berbak Propinsi JambiOleh: Helmi, Taufiqurrohman, Husni Thamrin ................. 131
3.3.1. Kondisi Hutan dan Kebijakan Pengelolaan Hutandi Propinsi Jambi ...................................................................... 131
xii
1. Kebijakan Eksploitatif Pengelolaan Hutan ................... 1312. Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi:
Pemanfaatan dan Ancaman .............................................. 135
3.3.2. Perlindungan dan Pengelolaan Hutandi Propinsi Jambi ...................................................................... 1401. Aktivitas Pelestarian Fungsi Hutan dan Pengelolaan
Hutan Berbasis Masyarakat di Propinsi Jambi .............. 140A. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan .. 140B. Restorasi Ekosistem ..................................................... 142
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jambi ....... 145
3.3.3. REDD ..................................................................................... 154
Bagian KeempatApa yang Terjadi dan Bagaimana ke Depan4.1. Riau ............................................................................................. 1654.1.1. Apa yang Terjadi ? ............................................................... 1654.1.2. Bagaimana ke Depan ........................................................... 167
Daftar Tabel, Grafik,Gambar, dan Box
Tabel 1. Indikasi Luas Lahan yang Perlu Direhabilitasi diIndonesia
Tabel 2. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar KawasanHutan per Propinsi di Indonesia
Tabel 3. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar KawasanHutan menurut Sebaran Wilayah Kerja BP DAS diIndonesia
Tabel 4. Profil Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit BalingTabel 5. Dampak Ekologis Lubuk Larangan IndarungTabel 6. Aspek-Aspek Kegiatan Reboisasi dan PenghijauanTabel 7. Deskripsi Anggaran Dana Proyek Rehabilitasi Hutan
di RiauTabel 8. Perkembangan Kegiatan Penanaman Program Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di PropinsiRiau Tahun 2003 s/d 2006
Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Bangunan Konservasi TanahProgram Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006
Tabel 10. Distribusi Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi(DAK-DR) dan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi(DBH-DR) di Propinsi Riau Tahun 2001 s/d 2009
Tabel 11. Distribusi Lokasi Pelaksanaan Proyek GN-RHL di RiauTahun 2004
Tabel 12. Sebaran Lokasi dan Luas Target GN-RHL perKabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun2007/2008
Tabel 13. Luas Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Propinsi
xiii
Sumatera BaratTabel 14. Perbandingan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan
menurut Rencana dan Realisasinya di Propinsi SumateraBarat
Tabel 15. Data Sebaran, Luas, dan Kandungan Karbon LahanGambut di Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2002
Tabel 16. Ancaman dan Gangguan yang Teridentifikasi di Daerahini adalah Penebangan Liar, Pengumpulan GetahJelutung, Pencarian Ikan, Perburuan Fauna (ular phyton)
Grafik 1. Peruntukan Kawasan di Propinsi RiauGrafik 2. Tutupan Hutan di Atas Tanah Gambut dan Non Gambut
di dalam Daratan Utama di Propinsi Riau Kurun Waktu1982-2007
Grafik 3. Daftar Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan denganDana DAK - DR Tahun 2003
Grafik 4. Perbandingan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan diPropinsi Riau dengan Dana DAK-DR Tahun 2003
Gambar 1. Perbandingan Peta Tutupan Hutan Riau pada 1982 dan2007
Gambar 2. Peta Survei Pembukaan Lahan di Rimbang Baling
Box 1. Prosesi Aktivitas PeladanganBox 2. Sanksi Pelanggaran Pantang Larang di Lubuk Larangan
Box 3. Proyek Rehabilitasi Hutan Riau Diminta Distop
xiv
Daftar Wawancara
• Bustamir, Khalifah Kuntu, Kampar Kiri, 7-12 Maret 2010
• Iskandar, Tokoh Masyarakat Pangkalan Indarung, 12-13 Maret2010
• Japri, Tokoh Adat Kuntu, Kuntu, 7-8 Maret 2010
• Yusman, Ketua Adat Batu Sanggan, 10 Maret 2010
xv
Latar BelakangPada tahun 2006 Kementerian Kehutanan mengumumkan
perubahan penutupan lahan dari hutan menjadi tidak berhutan seluas42,263 juta ha. Sebagian besar luasan tersebut (36%) telah berubahmenjadi lahan alang-alang sedangkan 26% merupakan lahanpertanian, dan sisanya terdiri dari semak, lahan basah (wetland),perumahan, dan penggunaan lainnya. Sedangkan laju kerusakanhutan Indonesia mencapai 1,1 juta hektar per tahun. “Sementarakemampuan pemerintah melakukan rehabilitasi hanya 500 ribuhektar per tahun,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup GustiMuhammad Hatta di Banjarmasin, Jumat (27/11)1.
Di lain pihak, pemerintah mulai menyadari adanya lahan-lahankritis di Indonesia. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yangtelah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehinggakehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendalierosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon.Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikansebagai : sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal.Berdasarkan kriteria tersebut, luas lahan kritis di Indonesia pada tahun2008 tanpa DKI Jakarta seluas ± 77.806.881 ha yang terdiri dari: 1)sangat kritis : 6.890.567 ha., 2) kritis : 23.306.233 ha, 3) agak kritis :47.610.081 ha. Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yangtelah ditentukan oleh Departemen Kehutanan untuk direhabilitasiadalah : 1) Dalam kawasan hutan : 59.170.700 ha dan Luar Kawasanhutan : 41.466.700 ha2.
Situasi yang tergambar di atas merupakan dampak dari eksploitasihutan secara besar-besaran yang dilakukan sejak lama. Eksploitasihutan besar-besaran dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun
1 Edan! 1,1 Juta Hektar, Laju Kerusakan Hutan Indonesia, Jumat, 27 November 2009 00:00, http://www.gibbon-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aedan-11-juta-hektar-laju-
kerusakan-hutan-indonesia&catid=3%3Aberita-lingkungan&Itemid=1&lang=en2 Kemenhut, 2009. Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial, Statistik Kehutanan Indonesia 2008
REDD: Antitesis Reboisasi?
03Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
1967 Tentang Kehutanan dan diikuti dengan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan HakPemungutan Hasil Hutan.
Pada penjelasan umum UU No. 5 tahun 1967 tentang kehutanandijelaskan bahwa penggalian sumber kekayaan alam yang berupa hutanini secara intensif, adalah merupakan pelaksanaan Amanat PenderitaanRakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunanekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kiranya perlu mendapat perhatian, bahwa ruang lingkup kegiatankehutanan pada waktu ini jauh lebih luas dari pada waktu-waktuyang lampau, berhubung dengan:1. Kegiatan pembangunan di mana-mana serta makin bertambahnya
kebutuhan penduduk akan peralatan rumah tangga yang selalumembutuhkan kayu banyak sekali, sehingga kebutuhan akan kayuselalu meningkat dengan pesat;
2. Makin majunya ekspor hasil hutan serta makin banyaknyapermintaan dari luar negeri;
3. Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagaibahan baku, antara lain:a. industri plywood, hardboard dan bahan-bahan untuk prefabricated
houses, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupununtuk diekspor;
b. industri pulp sebagai bahan baku untuk industri dalam negeriserta sebagai bahan setengah jadi untuk diekspor;
c. industri rayon untuk bahan sandang dan lain-lain.4. Bantuan yang dapat diberikan oleh kehutanan berhubung dengan
makin berkembangnya pengusahaan sutera alam oleh pemerintahbersama-sama dengan rakyat;
5. Makin majunya pariwisata di negara kita, antara lain wisatatamasya, wisata buru, dan wisata ilmiah, di mana kehutanan dapatmemberikan sumbangannya yang sangat besar;
6. Saham yang dapat diberikan oleh kehutanan dalam rangkapelaksanaan rencana pembangunan semesta dan pelaksanaan
REDD: Antitesis Reboisasi?
04 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
transmigrasi sebagai proyek nasional.Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, sampai pada tahun 1995
paling sedikit ada 586 konsesi HPH dengan luas keseluruhan 63 juta ha,atau lebih separuh dari luas hutan tetap, baik yang dieksploitasi perusahaanswasta maupun BUMN3. Hariadi Kartodihardjo dan Hira Jamtanimencatat, sampai pertengahan tahun 1990-an, terdapat 10 perusahaanyang menguasai 228 HPH, meliputi 27 Juta ha hutan alam produksi atau45 % dari 60 juta ha hutan yang dialokasikan untuk HPH. Sepertitercantum pada table 2.2, kelompok pengusaha ini mempunyai 48perusahaan kayu lapis dari 132 industri kayu lapis pada tahun 1990, ataukurang dari 40 % kapasitas produksi industri kayu panel nasional4.
Kebijakan pemanfaatan komoditas kayu hutan alam secara besar-besaran telah menyebabkan kerusakan yang mendorong terjadinyadampak-dampak negatif. Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesiamengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonominasional, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi sistem yangdominan dalam memanfaatkan hasil hutan dari hutan alam. TataGuna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata RuangWilayah Propinsi (RTRWP), digunakan untuk merancang danmengendalikan pembangunan HPH, HTI, dan perkebunan, terutamaperkebunan besar, agar dapat meminimumkan dampak negatifterhadap lingkungan dengan cara sedikit mungkin mengkonversihutan alam. Dalam pelaksanaannya, HPH telah mendahului sebagaipenyebab degradasi hutan alam. Degradasi ini semakin besar ketikapada tahun 1990 pemerintah mengundang swasta untuk melakukanpembangunan HTI melalui sejumlah insentif. Demikian pulatingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan denganmengkonversi hutan5.
3 FWI, 2004. Sejarah Penjarahan Hutan Nasional, intip hutan | Februari 20044 Kartodihardjo, Hariadi & Hira Jamtani, 2006. Politik Lingkungan dan kekuasaan di Indonesia, Equinox
Publishing, Jakarta, hlm 27-28.5 Kartodihardjo, hariadi & Agus SuprionoDampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi
Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia, CIFOR, Occasional Paper No. 26(I), Jan.2000, hlm 1
REDD: Antitesis Reboisasi?
05Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Meninjau Kisah Penghutanan KembaliMenyikapi kerusakan hutan alam tersebut, pemerintah kemudian
mengeluarkan kebijakan perlindungan hutan dan penghutanankembali. Salah satu program yang dikembangkan pemerintah padaera Orde Baru adalah program Inpres Penghijauan dan Reboisasi.Program Inpres Penghijauan dan Reboisasi yang merupakan salahsatu program pada sektor lingkungan hidup, telah dimulai sejaktahun 1969. Program ini secara umum bertujuan untuk memulihkankemampuan hutan dan tanah yang rusak agar lebih produktifkembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsilingkungan hidup. Daerah atau areal yang ditangani oleh programini adalah daerah-daerah pada hutan lindung (untuk reboisasi) danlahan kritis di beberapa daerah aliran sungai/DAS (untukpenghijauan). Sedangkan kegiatan reboisasi bertujuan untukmempertahankan mutu hutan lindung dan diharapkan dapatmeningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan lindung. Kegiatanprogram penghijauan dan reboisasi ini merupakan suatu gerakanmasyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.Pada awal pelaksanaan program, bantuan ini merupakan InpresPenghijauan dan Reboisasi yang bersifat sektoral (specific grant) dengankoordinasi instansi teknis Departemen Kehutanan. Dalamperkembangan waktu sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerahtingkat II, program Inpres Penghijauan dan Reboisasi telahmengalami perubahan kebijaksanaan. Mulai tahun pertamapelaksanaan Repelita VI, Inpres Penghijauan dan Reboisasi diubahmenjadi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang termasuk dalamProgram Bantuan Pembangunan Daerah (Khusus) Dati II. Hal inisesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkanbantuan pembangunan ke daerah tingkat II secara langsung namundengan arahan dan pembinaan teknis dari instansi pusat6.
6 Laporan Pembinaan Perencanaan Program Penghijauan Dan Reboisasi, http://regionaldua.tripod.com/hijau.html
REDD: Antitesis Reboisasi?
06 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Di sisi lain, pada sektor industry perkayuan, pemerintah menaruhharapan akan adanya proses penghutanan kembali pasca penebangan.Akan tetapi harapan itu sulit terwujud sehingga kemudian pemerintahsecara tidak langsung mengambil alih tanggung jawab penghutanankembali pasca penebangan hutan oleh perusahaan tersebut. Lahirnyapungutan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) tahun 1979/1980 sebenarnyaadalah berdasarkan hasil pemantauan pemerintah ketika itu, yangmenyimpulkan bahwa pada umumnya para pemegang hak pengusahaanhutan (PPHPH) atau sekarang disebut IUPHHK dianggap engganmelaksanakan penanaman (tepatnya adalah pembinaan) hutan di arealkerjanya. Sebagai dana jaminan, para pemegang ijin UPHHK(PIUPHHK) sebenarnya bisa berhak untuk menerima kembali DJRyang telah disimpannya di kas pemerintah apabila mereka bisamembuktikan kemampuannya melaksanakan pembinaan hutan untuktujuan kelestarian hutannya. Sebaliknya, bagi PIUPHHK yang tidakmampu melaksanakan reboisasi di areal kerjanya, dana DJR yang telahdisetorkannya akan tetap dipegang pemerintah (tanpa mengubah tujuanDJR yaitu untuk digunakan bagi pembiayaan pembinaan hutan padaareal HPH yang bersangkutan). Setelah Dana Reboisasi masuk ke dalamAPBN, nampaknya pengertian dana cadangan penyusutan aktiva hutanterkesan nyaris berubah menjadi “pendapatan pemerintah (PNBP)”seperti tercermin dalam ketentuan alokasi penggunaannya yangkemudian masuk ke dalam kategori “bagi hasil” antara pemerintahpusat dengan pemerintah daerah penghasil (periksa Undang-undangnomor 33). Perubahan penafsiran Dana Reboisasi dari yang semulabersifat teknis yakni merupakan cadangan biaya penyusutan tegakanhutan, menjadi dianggap sebagai pendapatan Pemerintah (PNBP) inilahsebenarnya yang merupakan dampak kesalahan penafsiran DR yangpaling berbahaya bagi kelestarian hutan, terutama di sektor PIUPHHK7.
Selama Orde Baru dana reboisasi dialokasikan untuk berbagaikepentingan, baik kepentingan kehutanan maupun kepentingan lainnya.
7 P.Warsito. Sofyan, Dana Reboisasi (DR) sebagai sumber dana pembinaan hutan di areal kerja IUPHHK(HPH) Tidakkah Boleh ?, hlm 2 dan 10
REDD: Antitesis Reboisasi?
07Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Salah satu kasus pengalokasian dana reboisasi yang cukup kontrofersialadalah ketika pada bulan Juni tahun 1994, Presiden RI (Suharto)mengeluarkan Keppres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjamankepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat TerbangNusantara (PT. IPTN) yang isinya tentang pemberian pinjaman tanpabunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400 M yang diambil dari hasilbunga/jasa giro dana reboisasi. Kasus lain yaitu pada tanggal 10Desember 1996 Presiden mengeluarkan Keppres No. 93 tahun 1996tentang Bantuan Pinjaman kepada PT Kiani Kertas yang berisi tentangpemberian bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas sebesar 250 milyarrupiah. Bantuan tersebut diambil dari Dana Reboisasi dan digunakanuntuk membantu penyelesaian pembangunan pabrik kertas yangberlokasi di Propinsi Kalimantan Timur. Akibat peminjaman DanaReboisasi untuk pendirian pabrik Pulp dan Kertas PT. Kiani Kertastelah menimbulkan preseden yang buruk. Terbukti dengan adanyapengajuan dari 11 perusahaan lain untuk meminjam Dana Reboisasibagi pembangunan pabrik pulp dan kertas. Kedua kasus ini kemudiandigugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepengadilan dengan dasar Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.
Christopher Barr dan kawan-kawan mencatat,during both the Soeharto and the post-Soeharto periods, effective utilizationof the DR has been undermined by weak financial management andinefficient revenue administration by institutions. Corruption and fraudhave undermined major DR-funded investments in reforestation and forestrehabilitation during both the Soeharto and the post-Soeharto periods,resulting in substantial losses of state financial assets and forest resources8.
Meskipun terdapat kebijakan-kebijakan perlindungan maupunpenghutanan kembali, tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa kegiatan
8 Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. and Komarudin, H. 2010 Financial governance and Indonesia’sReforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: a political economic analysis oflessons for REDD+. Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, Indonesia. Hlm 56-58
REDD: Antitesis Reboisasi?
08 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
penghutanan kembali ini tidak berhasil maksimal. Pada tahun 2000,Departemen Kehutanan menyelenggarakan lokakarya MoratoriumKonversi Hutan Alam dan Penutupan Industri Pengolahan Kayu SaratHutan. Lokakarya ini menyimpulkan bahwa kerusakan sumber daya hutanjuga disebabkan oleh kapasitas industri perkayuan dan pulp yang jauhmelebihi kemampuan sumberdaya hutan dalam menghasilkan bahan bakukayu secara lestari. Pada masa krisis (1996) industri pengolahan kayupertukangan skala menengah dan besar, dan industri pulp, membutuhkanmasing-masing 24 juta m3 dan 15 juta m3. Sedangkan kebutuhan untukindustri kecil kayu gergajian diperkirakan sebesar 9,4 juta m3. Padahalkemampuan hutan alam menyediakan bahan baku secara lestaridiperkirakan tidak lebih besar dari 22, 5 juta m39.
Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah masalah pengalokasiandana reboisasi. Terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaannya.Kasus HPH dan Dana Reboisasi hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli2000 tentang penggunaan Dana Reboisasi mengungkapkan ada 51 kasuskorupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi MasyarakatTransparansi Indonesia)10. Terakhir, pada tahun 2009 Menteri Kehutananmelaporkan progress kebijakan kehutanan yang memuat pelaksanaankebijakan tentang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
Rehabilitasi & Konservasi Sumber Daya Hutan11
Gerakan Penanaman SerentakKerjasama Rehabilitasi Lahandan Konservasi Sumber Daya
Hutan Antara Dephut
1. Penanaman serentak 79 juta bibitpohon tahun 2007, realisasi 86,9juta batang;
1. Kerjasama Dephut dengan TNIAD ditandatangani oleh Menhutdan KASAD di Jakarta tanggal
9 http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/63810 Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia, Monday, October 25, 2004 http://
kumpulanperkarakorupsi.blogspot.com/2008/08/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html11 Kaban,M.S., Progres Kebijakan Departemen Kehutanan Lima Tahun Terakhir Senin, 31 Agustus 2009,
(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3936&Itemid=286)
REDD: Antitesis Reboisasi?
09Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
2. Gerakan perempuan menanamdan pelihara pohon sebanyak 10juta batang, realisasi 14,1 jutabatang;
3. Penanaman kemitraan dengan 32ormas sebanyak 3,2 juta batang;
4. Pada tanggal 28 Nopember 2008di Cibinong Bogor, Presidentelah mencanangkan Hari Mena-nam Pohon Indonesia tanggal 28Nopember dan Bulan MenanamNasional bulan Desember. Se-kaligus memulai penanamanserentak 100 juta pohon diseluruh Indonesia;
5. Wakil Presiden Jusuf Kalla akanmemimpin Gerakan Aksi Pena-naman Pohon di Kampung Ge-dong, Desa Ciuyah, KecamatanSajirah, Kabupaten Lebak, Pro-pinsi Banten, tanggal 23 De-sember 2008, bertepatan denganBulan Menanam Pohon Nasionalbulan Desember;
6. Semangat dan kerja keras rakyatIndonesia telah mendapat penga-kuan dan penghargaan inter-nasional atas keberhasilan dalampenyelamatan lingkungan hidupdan pengurangan dampak pema-nasan global yang diterima tgl 5Juni 2008 melalui MenteriKehutanan dan Ibu Ani Yudho-yono berupa Certificate of GlobalLeadership dari United NationEnvironment Programme(UNEP).
28 April 2008 (berlaku selama 3tahun). Kerjasama Kemitraandengan Perguruan Tinggi yaituUniversitas Nusa Cendana(NTT), Universitas Mataram(NTB), Universitas Medan Area(Sumut);
2. Kerjasama Indonesia denganJepang (Sumitomo ForestryCo.Ltd) dalam penghutanankembali (reforestasi) melaluimekanisme A/R CDM di ka-wasan Taman Nasional BromoTengger;
3. Kerjasama bilateral Indonesiadengan Timor Leste bidangkehutanan, salah satunya adalahReforestation and forest rehabilitation(Agro forestry and community forestry).
REDD: Antitesis Reboisasi?
10 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Hutan dan Perubahan IklimPada perkembangannya, hutan tidak hanya sebagai pemasok
komoditas kayu tetapi telah berkembang pada pemasok Non TimberForest Product, Biodiversity dan terakhir berupa jasa lingkungan lainnya.Dalam kerangka jasa lingkungan, dunia kehutanan mengembangkanmekanisme penghargaan dan pembayaran jasa lingkungan kepadapara pengelola hutan. Meskipun konsep penghargaan jasa lingkunganini dikembangkan oleh para ahli di lapangan, dikalangan masyarakatyang berhubungan dengan hutan, mekanisme ini telah lamaberkembang, tumbuh dalam kebudayaan mereka. Seperti di Bali,pada sebuah kawasan, masyarakat di hilir memberikan sejumlahpadi kepada masyarakat hulu sebagai penghargaan atas kegiatanmasyarakat hulu yang menjaga hutan agar air tetap mengalir kesawah-sawah masyarakat hilir.
Isu pemanasan global menjadi fokus dunia tahun 1992 melaluiUnited Nations Convention on Climate Change. Konvensi perubahaniklim PBB ini kemudian ditindaklanjuti dengan Protokol Tokyo padatahun 1997 dan mulai berlaku 16 Febuari 2005. Dalam perjalanannyahutan sebagai sebuah ekosistem kemudian disadari mengandungbanyak carbon yang sangat berkontribusi kepada perubahan iklim.Salah satu penelitian penting yang menjadi rujukan adalah SternReview pada tahun 2006 yang membicarakan deforestasi dandegradasi hutan berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisiglobal, dari jumlah tersebut 75% nya berasal dari negara-negaraberkembang. Sebaliknya hutan juga ditenggarai memilikikemampuan untuk menyerap carbon yang menyebabkan terjadinyaperubahan iklim. Clean Development Mechanism (CDM) kemudiandiperkenalkan sebagai sebuah mekanisme baru untuk membantunegara-negara maju menurunkan tingkat emisinya.
CDM adalah sebuah mekanisme di mana negara-negara yangtergabung di dalam Annex 1, yang memiliki kewajiban untukmenurunkan emisi gas-gas rumah kaca sampai angka tertentu per
REDD: Antitesis Reboisasi?
11Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
tahun 2012 seperti yang telah diatur dalam Protokol Kyoto,membantu negara-negara non-Annex 1 untuk melaksanakan proyek-proyek yang mampu menurunkan atau menyerap emisi setidaknyasatu dari enam jenis gas rumah kaca. Negara-negara non-Annex 1yang dimaksud adalah yang menandatangani Protokol Kyoto namuntidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisinya. Satuanjumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang bisa diturunkandikonversikan menjadi sebuah kredit yang dikenal dengan istilahCertified Emissions Reduction (CERs) - satuan reduksi emisi yang telahdisertifikasi. Negara-negara Annex 1 dapat memanfaatkan CER iniuntuk membantu mereka memenuhi target penurunan emisi sepertiyang diatur di dalam protokol (UNFCCC)12.
Perjalanan CDM ternyata tidak panjang. Sulitnya mekanismepengembangan proyek CDM membuat upaya-upaya ke arah itumenjadi tidak menarik. Tetapi perundingan-perundingan perubahaniklim tetap menempatkan hutan sebagai satu faktor penting bagimitigasi perubahan iklim. Pada COP 11 UNFCCC bulan Desember2005, Papua Nugini, Costa Rica dan sekelompok negara-negara yangmemiliki hutan tropis (Koalisi Bangsa-Bangsa untuk Hutan Hujan,CfRN) mengajukan sebuah proposal mengenai pengurangan emisidari deforestasi (RED) di negara-negara berkembang denganmenggunakan pendekatan emisi nasional. Proposal ini disambutbaik oleh banyak negara, terutama karena adanya fokus baru, yangmemecahkan berbagai permasalahan dari diskusi ‘penghindarandeforestasi’ yang ada sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkatproyek atau pendekatan sub-nasional. COP merujuk isu tersebutkepada Badan Tambahan untuk Masukan Ilmiah dan Teknis(Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice -SBSTA), yang telahmenerima banyak usulan dan mengadakan dua lokakarya (FCCC/SBSTA/2006/10 dan FCCC/SBSTA/2007/3). Ketua SBSTA telahmengusulkan rancangan kesimpulan dan menyiapkan rancangan
12 Institute for Global Environmental Strategies, 2005, Panduan Kegiatan MPB di Indonesia, hlm 23
REDD: Antitesis Reboisasi?
12 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
keputusan mengenai RED untuk didiskusikan di COP 13 di Bali onRED to be discussed at COP13 in Bali (FCCC/SBSTA/2007/L.10)13. Dalam perjalanannya kemudian RED berkembang menjadiREDD dengan penambahan kata Degradation dan bahkan lebihberkembang lagi dengan penambahan REDD + (plus) dan REDD++ (plus-plus).
Pasca pertemuan Bali, juru bicara untuk bank investasiperdagangan karbon Inggris, Climate Change Capital, memprediksibahwa penetapan target-target emisi yang mengikat akanmenciptakan ‘peluang pasar yang sangat besar’. Ia mengatakan bahwakita kemudian akan melihat “kekuatan uang swasta yang mengaliruntuk tujuan moral”. Tapi seberapa jauh sektor swasta dapatdipercaya? Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwamencampurkan keuntungan dan moral tidaklah mudah dalampraktiknya, terutama bila yang menjadi taruhan adalah tanahpenduduk, sumber daya alam dan mata pencaharian. Perusahaanumumnya lebih tertarik pada keuntungan (profit) jangka pendekdaripada perubahan iklim jangka panjang14.
Diskursus-diskursus penting mengenai fungsi hutan bagi mitigasiperubahan iklim yang terurai di atas mengantarkan kita pada satupokok masalah yaitu bagaimana melindungi hutan yang memilikifungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perdebatan mekanismeREDD yang pada akhirnya melibatkan pasar sebagai kelompok yangmengambil manfaat dari transaksi iklim dan mungkin jugamenggunakan kekuatan memaksanya untuk memaksakanterlaksananya perlindungan hutan, menimbulkan pertanyaan pentingyaitu apakah mekanisme voluntary untuk perlindungan hutan danpenghutanan kembali yang berjalan selama ini telah gagal dan tidakdapat dipercaya.
Selanjutnya pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa
13 Climate Action Network (CAN), November 2007, Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi(REDD), Dokumen Diskusi, hlm 5
14 DTE, 2009, Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan, KIPPY Print Solution, Hlm 31
REDD: Antitesis Reboisasi?
13Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
semua kebijakan perlindungan hutan maupun penghutanan kembaliseolah tidak bekerja sehingga kerusakan hutan sampai hari ini tidakdapat dihentikan. Apakah politik hukum yang dikembangkan dalampengelolaan hutan memang tidak mendukung pada keutuhan hutan,apakah ada faktor-faktor non kehutanan yang mempengaruhi tidakefektifnya kebijakan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakahmekanisme-mekanisme penghargaan lokal terhadap masyarakat yangmenjaga keutuhan hutan sehingga tetap memberikan fungsilingkungan tetap berlangsung sampai hari ini.
Pengorganisasian BukuSepanjang tahun 2010, Scale Up memfasilitasi studi di beberapa
lokasi di tiga propinsi di Sumatera yakni Riau, Sumatera Barat, danJambi. Studi ini bertujuan untuk: 1). Memetakan kebijakan yangberhubungan dengan eksploitasi sumber daya hutan dan mem-bandingkannya dengan kebijakan perlindungan dan penghutanankembali: 2) Mengkaji politik hukum perlindungan hutan dankebijakan penghutanan kembali, 3) Melihat kenapa banyak kebijakanpenghutanan kembali tidak menghasilkan hasil yang maksimalsehingga REDD seperti menjadi pilihan akhir untuk penyelamatanhutan, dan: 4). Mendokumentasikan bagaimana mekanismepenghargaan lokal terhadap penyelamatan hutan.
Studi ini berangkat dari kegelisahan yang diwakili olehpertanyaan-pertanyaan apakah bagaimana sebenarnya implementasidari kebijakan penghutanan kembali di Indonesia. Jika kebijakanpenghutanan kembali itu gagal atau paling tidak, tidak terlalumaksimal, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Buku ini diorganisasikan dengan pendekatan semi formal denganmaksud mengubah kesan kaku dari sebuah senarai laporan penelitian.Meskipun bagian-bagian dari buku ini tidak dibagi atas Bab perBab dengan angka formal, namun sejatinya bagian per bagian daribuku ini memaparkan sebuah alur yang saling berhubungan yaitu
REDD: Antitesis Reboisasi?
14 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dimulai dengan deskripsi kebijakan penghutanan kembali dalampolitik hukum kehutanan. Bagian selanjutnya mencoba memaparkantemuan-temuan lapangan tentang bagaimana dinamika pengelolaanhutan dan program penghutanan kembali di lokasi-lokasi terpilih ditiga propinsi di Sumatera. Terakhir buku ini mencoba memaparkankesimpulan dari temuan-temuan lapangan dan rekomendasi yangingin disampaikan oleh tim studi.
REDD: Antitesis Reboisasi?
15Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
1. Konsep Penguasaan Sumber Daya AlamKepemilikan sumber daya alam termasuk hutan bersifat komplek.
Di satu pihak ada bagian dari ekosistem yang dapat memberi manfaatatau mendatangkan kerugian bagi masyarakat banyak (public benefit/cost), di pihak lain sumber daya alam dapat berupa komoditi (privategoods) yang hanya dinikmati perorangan. Karena itu tersedia pilihan-pilihan bentuk hak-hak (rights) terhadap sumber daya alam, berkisardari yang dikuasai negara (state property), diatur bersama di dalamsuatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu (common property),atau berupa hak individu (private property).1
Baumol dan Oates pada tahun 1988, menyatakan : dalamperjalanannya, di mana paham neoliberalisme dan demokrasimendominasi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang,termasuk Indonesia, konsep pemilikan individu terhadap sumberdaya alam menjadi arus utama yang melandasi kebijakan ekonomipolitik suatu negara. Dalam kaitan ini, kebijakan perumusankebijakan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkunganseringkali terpisah dari atau tidak mempertimbangkan common property.Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hanya membahassiapa yang bertanggungjawab terhadap ekstenalitas.2
Sementara itu, kesalahan alokasi sumber daya alam dianggapsebagai akibat domain publik atas sumber daya yang bersifat openaccess. Oleh karena itu pemecahan yang diajukan berkisar padapenetapan pajak/retribusi dan privatisasi. Keduanya dianggap dapatmenyelesaikan eksploitasi sumber daya secara berlebihan danmenginternalisasi eksternalitas melalui alokasi hak secara eksklusif.Pendekatan ini kerap digunakan untuk menangani masalahlingkungan akibat pencemaran limbah beracun yang berasal daripabrik. Hal ini juga diterapkan untuk mengendalikan kerusakan
1 Lihat, pada Haryadi Kartodiharjo dan Hira Jhamhani, Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia,Equinox Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 63.
2 Ibid.
REDD: Antitesis Reboisasi?
19Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
sumber daya alam dalam arti luas.Bentuk kebijakan suatu negara dapat ditentukan oleh pengertian
dan asumsi dasar tentang sumber daya alam yang sedang dibahas.Pengertian dan asumsi dasar tersebut akan menentukan siapapemilik, pengguna, pengatur sumber daya, siapa yang mengendalikanakses pihak lain jika sumber daya rusak, dan siapa mendapatkanmanfaat dari sumber daya tersebut.3
Jika sistem hukum dan pemerintahan tidak sejalan denganimplementasi di lapangan, biasanya masyarakat menjadi pihakmarginal. Pada konteks pengelolaan Taman Nasional, masyarakatsekitar kawasan dianggap sebagai ancaman, sehingga harus ditutupaksesnya. Pemerintah sebagai pelaksana public property menjadi pihakyang menganggap paling berhak mengelola.
Di tengah implementasi kebijakan yang eksploitatif, ada kebijakandan kejadian-kejadian yang bersifat paradoksial. Misal penetapansuatu kawasan menjadi suaka margasatwa dan suaka alam untukmelindungi flora dan fauna tertentu yang seharusnya dapatdipertahankan, tetapi kenyataannya tidak demikian.
Kebijakan yang eksploitatif juga merusak modal sosialmasyarakat, di mana kebijakan nasional belum bertumpu padapenyeimbangan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitukelestarian modal alam, modal individu, modal sosial, dan modalbuatan. Misalnya tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam.Kerusakan modal alam dan modal sosial sudah sampai pada suatutitik yang mengarah pada kebangkrutan modal itu sendiri.
Ketidakseimbangan kondisi pilar pembangunan berkelanjutantersebut berakibat tidak saja kerusakan modal alam, namunberdampak negatif pada kondisi sosial. Masyarakat yang seharusnyamendapat manfaat atas pengelolaan hutan, justru menjadi korbandari kerusakan tersebut. Mulai dari tidak dapat lagi menggunakan
3 White, Ben, Land and resouce tenure: brief notes, Paper presented at international Conference on LandResource Tenure in Indonesia: Questioning The Answer, Jakarta 11-13, Oktober 2004.
REDD: Antitesis Reboisasi?
20 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
air yang telah tercemar, sampai pada penyakit yang harus dideritaakibat pencemaran lingkungan.
2. Kebijakan Umum Pengelolaan HutanUU Kehutanan yang berlaku sebelum dan sesudah reformasi
telah mengelompokkan hutan berdasarkan status dan fungsinya.Berdasarkan status, UU kehutanan membaginya ke dalam HutanNegara dan Hutan Hak. Sebagai konsekuensi dari hak menguasainegara atas tanah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, UU Kehutanan memberikan kewenangan kepadapemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagaikawasan hutan dan bukan kawasan hutan (Pasal-Pasal 4 ayat (2)huruf b). Adapun yang dimaksud dengan Hutan Negara oleh UUini adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hakatas tanah. Sedangkan hutan hak disebut sebagai hutan yang beradapada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah yangdimaksud oleh UU kehutanan ini sudah barang tentu mengacukepada hak-hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA N0.5tahun 1960. Karena hak adat bukan termasuk jenis hak-hak yangdiatur dalam UUPA, maka oleh UU Kehutanan, hutan adatdiposisikan sebagai “Hutan Negara yang secara kebetulan” lokasinyaberada di wilayah persekutuan masyarakat hukum adat.
Dengan demikian penyebutan hutan adat bukanlah bermaknapengakuan status kepemilikan dan penguasaan masyarakat hukumadat atas hutan yang berada di lingkungan persekutuan mereka.Pemangku kewenangan penguasaan atas wilayah hutan tersebut,tetap berada pada Departemen Kehutanan. Makna hutan adatakhirnya direduksi sekedar menjadi jenis hak pemanfaatan yangdiberikan oleh negara kepada persekutuan masyarakat di mana hutantersebut berada, berdasarkan skema perizinan. Pengaturan inimenjadi bibit konflik, yang belakangan berkembang dengan subur,hampir di seluruh wilayah kawasan hutan. Karena bagi masyarakat
REDD: Antitesis Reboisasi?
21Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
hukum adat, makna hutan adat adalah status hak dari hutan tersebutsebagai milik dan kuasa masyarakat hukum adat.
Berdasarkan fungsinya, UU Kehutanan membagi hutan ke dalamfungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pembagianhutan ke dalam 3 (tiga) fungsi ini memperlihatkan peran yang harusdisangga oleh hutan, baik dalam konteks ”negara” maupun dalamkonteks ”hutan sebagai satu kesatuan ekosistem” yang juga harusmampu memberikan perlindungan keselamatan bagi kehidupan.
Melalui fungsi produksi, kawasan hutan didorong untuk berperansecara ekonomik dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik pada kawasan hutan didorong untuksegera dikonversi menjadi rupiah, melalui eksploitasi besar-besaran.Karena kemampuan keuangan negara yang tidak cukup untukmembiayai kegiatan eksploitasi ini, pemerintah mendorong modal-modal swasta untuk mengerubuti hutan. Berbagai insentif baikkemudahan perizinan, kelonggaran kontrol, dan toleransi ataspelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukanoleh industri kehutanan diberikan.
Sejak pemberlakuan UU Kehutanan No. 5/1967 sampai tahun2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan arealhutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelahdikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomeratkehutanan (Awang : www.ugm.ac.id).
Wilayah-wilayah hutan yang mempunyai ciri-ciri spesifik/khas,ditetapkan menjadi hutan konservasi, yang berfungsi sebagai tempatpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosis-temnya. Di dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi ini,berlaku UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaHayati dan Ekosistemnya. Wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagaikawasan konservasi biasanya muncul dalam bentuk Taman Nasional,Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam.
Pengelolaan kawasan konservasi ini terbagi ke dalam beberapazona, dimana zona inti merupakan zona yang sama sekali tidak
REDD: Antitesis Reboisasi?
22 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
boleh ada aktivitas di dalamnya. Zona ini mesti memperolehpengamanan yang maksimum.
Wilayah-wilayah hutan yang memberikan perlindungan terhadapsistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memeliharakesuburan tanah, ditetapkan sebagai hutan lindung. Pada kawasanhutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, masih dimungkinkanuntuk melakukan aktifitas, sepanjang tidak merusak kemampuannyauntuk memberikan fungsi perlindungan pada wilayah sekitarnya. Diantara model pemanfaatan yang bisa dilakukan adalah pemanfaatankawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutanbukan kayu. Pelaksanaan model pemanfaatan ini dilakukan melaluimekanisme perizinan. Pemanfaatan tanpa izin atau pemanfaatan diluar model pemanfatan yang diizinkan termasuk pada pemanfaatanilegal. Terhadap pemanfaatan yang ilegal tersebut, ketentuan-ketentuanpidana kehutanan diterapkan.
3. Konsep dan Sejarah KonservasiPelaksanaan perlindungan alam sebelum merdeka dipelopori Dr.
S.H. Koorders, yang membentuk dan menjadi ketua TotNatuurbescherming (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda).Bekerjasama dengan ahli botani, Th Valeton, perkumpulan tersebutberjasa menerbitkan karya besar 13 jilid buku “Bijdragen tot de kennisder boomsoorten van Java,” merupakan inventarisasi jenis-jenis pohondari Jawa, yang dilakukan pada 1893 - 1914. Pada Maret 1913perkumpulan itu juga mengajukan usulan kepada pemerintah Belandauntuk menetapkan 12 lokasi sebagai cagar alam, diantaranya beberapadanau di Banten, Pulau Krakatau, Kawah Papandayan, SemenanjungUjung Kulon, Laut Pasir di Bromo, Pulau Nusa Barung, SemenanjungPurwo Blambangan, dan Kawah Ijen. Kawasan hutan di luar Jawayang diusulkan untuk dilindungi mencakup Gunung Kerinci pada1925, Gunung Leuser pada 1934 seluas 400.000 ha, serta beberapa
REDD: Antitesis Reboisasi?
23Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kawasan di Kalimantan dan Irian. Meskipun cagar alam dan kawasanperlindungan alam telah ditetapkan, namun tindakan tersebut berdirisendiri dan bukan akibat dari rancangan umum mengenai konservasialam yang dilakukan pemerintah.4
Gerakan konservasi tersebut nampaknya mengikuti pengem-bangan taman nasional pertama yang ditetapkan AS, yaitu TamanNasional Yellowstone pada 1872. Tujuan penetapan taman nasionaladalah memisahkan kawasan tertentu yang berfungsi sebagai sumberkeindahan antar generasi, dan tidak boleh diganggu, serta tidak bolehdieksploitasi. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan masyarakatyang telah menghuni kawasan tersebut sejak lama.
Selanjutnya pemerintah menerbitkan Ordonansi PerlindunganAlam tahun 1941. Walaupun tidak pernah diundangkan, sejak itu,wilayah di luar yang dikuasai negara juga boleh ditetapkan sebagaikawasan yang dilindungi dengan persetujuan pemilik hak. Dalamordonansi tersebut kawasan perlindungan juga termasuk kawasanterumbu karang di tepi pantai di mana masyarakat lokal mempunyaihak untuk menangkap ikan dan memungut hasil laut sejak dulu.
Perkembangan tersebut menggambarkan meskipun ada upayake arah konservasi, namun pendekatan yang digunakan bersifatparsial dengan mengutamakan konservasi biologi semata-mata, tanpamempertimbangkan peran dan posisi masyarakat lokal. Pendekatandemikian dilakukan tidak hanya pada masa penjajahan tetapi jugaditerapkan sesudah kemerdekaan.
Pada akhir 1970-an, Indonesia mulai mengikuti negara-negara laindengan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkanperlindungan dan pelestarian alam dalam bentuk yang relatif baru, yaitubentuk taman nasional. Yang diikuti waktu itu adalah prinsip-prinsip dasardari taman nasional pertama di dunia, Taman Nasional (TN) Yellowstonedi AS, dan prinsip-prinsip pokok yang sudah diterima di PersidanganUmum IUCN (The World Conservation Union) pada tahun 1969.
4 Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, op., cit., hlm. 20.
REDD: Antitesis Reboisasi?
24 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Prinsip-prinsip itu termasuk:1. Taman nasional harus mengandung “isi” istimewa, serta
keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh;2. Adanya sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif, di mana
satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak diubah karenaadanya eksploitasi dan pemukiman manusia;
3. Kebijaksanaan dan manajemen dipegang oleh pemerintah pusatyang mempunyai kompetensi sepenuhnya, yang harus segeramengambil langkah-langkah pencegahan atau meniadakan semuabentuk gangguan/pengrusakan terhadap ekosistem dan “isi”taman nasional itu.5Persoalan yang muncul atas prinsip di atas, kebutuhan-kebutuhan
dan hak-hak masyarakat setempat tidak diperhatikan. Dalam rangkapencegahan semua bentuk gangguan dan pengrusakan terhadaplingkungan alam, masyarakat setempat diusir oleh pemerintah. Pendudukasli dikeluarkan demi kepentingan konservasi Indonesia mengikuti pola-pola pengelolaan tersebut yang didukung oleh organisasi internasional.
Pada awal 1980-an sebuah laporan lapangan disiapkan oleh PBBuntuk Direktorat Jenderal Kehutanan. Laporan internasional itumendukung pemikiran bahwa masyarakat sekitar harus dikelola sajatanpa dilibatkan. Menurut laporan itu, ketidakadaan rasa hormatdan simpati terhadap tujuan-tujuan konservasi oleh masyarakatsekitar kawasan konservasi bisa diperbaiki sedikit dengan pendidikandan penyuluhan, tetapi satu-satunya solusi yang benar adalahangkatan perlindungan dan hukuman yang serius.6 Dalam halrencana pengelolaan, menurut yang ditulis waktu itu sama sekalibelum ada pembicaraan bersama pemerintah lokal.7 Masyarakatumum, yang kedudukannya di bawah tingkat itu, diabaikan lagi dan
5 Soewardi, H. 1978, Menyongsong Taman Nasional (National Park) di Indonesia, DirektoratPerlindungan dan Pengawetan Alam, Direkturat Jenderal Kehutanan, hal 4.
6 UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO) 1981, National Conservation Plan forIndonesia Volume III, laporan lapangan disediakan untuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan
Alam, Direkturat Jenderal Kehutanan, Bogor, bab 40, hal 3.7 Ibid, hlm. 1.
REDD: Antitesis Reboisasi?
25Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
tidak dianggap berperan dalam pengelolaan bahkan dari awalnyadalam perencanaan.
Memang menurut sejarah, masyarakat setempat tidak diberi suaradalam pengelolaan taman nasional. Pada awalnya dalam konseptaman nasional masyarakat setempat dianggap sebagai tidak ada,atau paling hanya sebagai sebentuk gangguan saja yang harusdihapus. Padahal, kehidupan masyarakat sangat tergantung dengansumber daya alam, salah satunya hutan.
Secara teori kelestarian ekosistem dan “isi”-nya taman nasional bagikita semua, bagi manusia, agar dapat dilaksanakan kegiatan perataankesejahteraan material dan spiritual.8 Maka secara teoritis, kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus diperhatikan. Kenyataannya, dalam rangkaperlindungan dan pengamanan taman nasional, masyarakat tidakdiperkenankan melakukan aktivitas di kawasan taman nasional.
Padahal, saat ini sudah banyak taman nasional di seluruh duniayang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkanmasyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. Keterlibatanmasyarakat membantu pihak konservasi untuk meningkatkankesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kawasan konservasi,menggunakan pengetahuan masyarakat yang mendalam tentanglingkungan alam, dan mengurangi ketergantungan masyarakat padasumber daya alam di kawasan konservasi dengan menaikkan tingkatekonominya. Kenaikan ekonomi itu tentu saja membantu masyarakatsetempat, kalau dilibatkan mereka juga bisa ikut berperan dalam prosespengelolaan taman nasional, dan kesejahteraannya akan lebih terjamin.
Pada tahun 1982, Kongres Dunia Taman Nasional (World Congresson National Parks) diadakan di Bali, dan pentingnya partisipasimasyarakat diakui dengan semangat.9 Pada Konferensi AnggotaKonvensi Keragaman Hayati Kedua yang diadakan di Jakarta pada
8 Hardjosentono, H.P. Kata Sambutan, dalam Soewardi, H. 19789 Putro, H.R. 2001, Participatory Management of National Park and Protection Forest: a NewChallenge in Indonesia, online, http://www.nourishin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdfdiakses 01/10/2004.
REDD: Antitesis Reboisasi?
26 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
tahun 1995, intinya termasuk keputusan melibatkan masyarakatsetempat dalam penetapan rencana kerjanya.10
Namun di Indonesia, seperti di seluruh dunia, peran masyarakatdiakui secara resmi tetapi pelaksanaan keputusan-keputusan itu jauhlebih lambat secara praktis. Walaupun demikian, Indonesia sudahmengimplementasikan pengelolaan partisipatif. Ada beberapa tamannasional yang sudah mendapatkan keuntungan dari keterlibatanmasyarakat dengan cara yang berarti.
Menjelang musim kemarau, bulan Juli dan Agustus tahun 2006,melalui iklan layanan masyarakat, Presiden dan Menteri Kehutananmelakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, “iniharus kita hentikan!” Ironis, kebakaran hutan dan pembakaran lahanterus terjadi hampir tidak terkendali. Penulis sendiri merasakandampak kebakaran tersebut. Asap yang memenuhi udara, sehingga
10 Wiryono, P. Kata Pengantar, dalam Widianarko, B. 1998, Ekologi dan Keadilan Sosial, Kanisius,Yogyakarta, hal 9.
REDD: Antitesis Reboisasi?
27Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Saat ini sudah banyak taman nasional di seluruh dunia yang sudahmelaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karenaadanya kesadaran akan manfaatnya. sumber : scale up
mengganggu arus penerbangan Jakarta-Sumatera.Memahami kondisi kerusakan hutan dan lahan, gerakan
konservasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyadaran.Gerakan tersebut harus mampu menciptakan kondisi masyarakatyang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Ketidakberdayaanmasyarakat berakar pada kemiskinan, baik alamiah maupunstruktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkankualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendahsehingga tidak mampu berproduksi. Kemiskinan struktural; adalahkemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkanoleh kurang tepatnya tatanan kelembagaan. Dalam hal ini, tatatankelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi ataukebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak pada masyarakatmiskin.
Di sinilah pentingnya politik hukum konservasi di Indonesia.Pemerintah sebagai pemiliki kewenangan seharusnya membentukdan memberlakukan kebijakan konservasi hutan yang didasarkanpada prinsip-prinsip keseimbangan dengan kepentingan peningkatankesejahteraan masyarakat.
4. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan
1). Kondisi Hutan dan Lahan saat Pencanangan GN-RHLSaat program ini dicanangkan, tingkat kerusakan hutan sudah
sangat mengkhawatirkan. Berbagai bentuk bencana ekologi sepertibanjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana lainnya yangditengarai sebagai akibat dari kerusakan hutan dan lahan sudahberulang di banyak tempat. Pada tahun 2002 total luas lahan yangperlu direhabilitasi berkisar 96,3 juta ha, dengan perincian 54,6 jutaha di dalam kawasan hutan, dan 41,7 juta ha di luar kawasan hutan.Rincian indikatif luas lahan yang perlu direhabilitasi diperlihatkanoleh tabel berikut.
REDD: Antitesis Reboisasi?
28 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sedangkan jumlah DAS kritis yang seharusnya menjadi lokasiGN-RHL kurang lebih 77,8 juta ha, dengan tingkat kekritisan 47,6juta ha agak kritis, 23,3 juta ha kritis, dan 6,8 juta ha sangat kritis.Lengkapnya luas lahan kritis per provinsi tergambar dalam tabelberikut.
Tabel 1. Indikasi Luas Lahan yang Perlu Direhabilitasi di Indonesia
REDD: Antitesis Reboisasi?
29Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 2. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar KawasanHutan per Provinsi di Indonesia
REDD: Antitesis Reboisasi?
30 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Besarnya angka luasan hutan dan lahan yang kritis selainmemperlihatkan pola pengelolaan hutan dan lahan yang eksploitatifbaik terhadap kayu maupun terhadap material lain yang terdapat didalam tanah, sekaligus memperlihatkan aspek kegagalan kegiatanperlindungan dan penghutanan kembali lahan-lahan yang sudahmengalami degradasi dan deforestasi.
Parahnya tingkat degradasi hutan dan lahan, yang ditengaraimencapai 43 juta ha, dengan kisaran laju deforestasi sebesar 1,6 – 2juta ha pertahun (Kep. Menko Kesra No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003), mungkin bisa disebut sebagai fakta yang dapatmengkonfirmasi tentang belum optimalnya kegiatan perlindunganhutan dan reforestasi yang selama ini dilakukan. Tanpamengenyampingkan penyebab lain yang mengakibatkan kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan tidak maksimal, program GN-RHL bisadisebut mengandaikan salah satu penyebab kegagalan tersebut adalahrendahnya koordinasi antar berbagai sektor dalam kegiatan
REDD: Antitesis Reboisasi?
31Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Eksploitasi hutan masih terus terjadi selama perlindungan hutan masihdilakukan setengah hati. Nilai ekonomi hutan yang cukup tinggi mendorongterjadinya eksploitasi yang mengabaikan nilai-nilai kelestarian hutan alam.sumber : scale up
rehabilitasi hutan dan lahan, yang sebelumnya hanya dikelola secarasektoral oleh Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan didaerah.
GN-RHL hendak menjadikan kegiatan rehabilitasi hutan danlahan sebagai gerakan nasional, di mana setiap sektor diasumsikanakan berkontribusi sesuai dengan lingkup kewenangan dankompetensi institusi masing-masing. Niatan ini terbaca dalam bagianlatar belakang Keputusan Menko Kesra No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003, yang menyebutkan : dengan mengingatrehabilitasi hutan dan lahan sebagai sesuatu yang sangat strategisbagi kepentingan nasional, maka rehabilitasi hutan dan lahan hendakdiarahkan sebagai sebuah gerakan yang berskala nasional yangdilakukan dengan terencana dan terpadu.
2) Kelembagaan GN-RHLUntuk memberi kerangka legal terhadap aspek keterpaduan
dalam kegiatan ini, Menko Kesra mengeluarkan SK No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003, yang salah satu isinya mengaturtentang pengorganisasian Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan danLahan dengan membentuk berbagai tim. Selain Keputusan MenkoKesra ini, Menteri Kehutanan juga mengeluarkan Peraturan MenteriKehutanan No. P.03/Menhut-V/2004, yang salah satu lampirannyamengatur mengenai kelembagaan. Pada intinya Keputusan MenkoKesra dan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut mengaturkelembagaan GN-RHL sebagai berikut :
a. Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasidan Reboisasi NasionalTim ini terdiri dari Pengarah yang diisi oleh 3 (tiga) Menteri
Koordinator yaitu Menko Kesra, Menko Perekonomian, dan MenkoPolkam. Selanjutnya ada ketua yang langsung dijabat oleh MenkoKesra dengan wakil ketuanya yaitu Menteri Kehutanan dan MenteriLingkungan Hidup. Seketaris dijabat oleh Sekretaris Bakornas dan
REDD: Antitesis Reboisasi?
32 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
wakil sekretaris dijabat oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan bidangstrategi pembangunan kehutanan. Tim koordinasi ini juga berisidua kelompok kerja yaitu kelompok kerja pencegahan kerusakanlinkungan yang personilnya terdiri dari Menteri Negara LingkunganHidup sebagai ketua, Menteri Kehakiman dan HAM, dan KepalaKepolisian RI. Kelompok kerja kedua adalah kelompok kerjapenanaman hutan dan rehabilitasi. Kelompok kerja ini terdiri dariMenteri kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Riset dan Teknologi,Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Keuangan,dan Panglima TNI. Dua kelompok kerja ini sesuai dengan ruanglingkup GN-RHL yaitu kegiatan pencegahan perusakan lingkungandan kegiatan penanaman hutan dan rehabilitasi.
b. Tim PengendaliTim ini terdiri dari tim pengendali tingkat pusat dan tim
pengendali tingkat propinsi. Tim pengendali tingkat pusatkeanggotaannya terdiri dari Kementerian/Departemen/NonDepartemen/Lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan GN-RHL. Tim ini bertugas untuk melakukkan koordinasi, me-nyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan bahan kebijakan,membina tim pengendali tingkat propinsi dan kabupaten/kota,memantau dan mengevaluasi serta melaporkan hasil-hasilpengendalian penyelenggaraan GN-RHL.
Sedangkan tim pengendali tingkat propinsi diketuai langsungoleh gubernur dengan keanggotaan yang terdiri dari unsurKehutanan, Kanwil Ditjen Anggaran, Lingkungan Hidup, Pertanian,Kimpraswil, Pendidikan, Pertanahan, TNI dan Kepolisian RI,Kejaksaan Tinggi dan LSM. Tim ini bertugas untuk melakukankoordinasi, mendorong partisipasi, pembinaan, pemantauan, danevaluasi serta melaporkan hasil pengendalian penyelenggaraan GN-RHL di wilayahnya. Dalam operasionalnya, tim ini dibantu olehsekretariat. Output kerja tim ini antara lain adalah terbitnya SK tim
REDD: Antitesis Reboisasi?
33Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pengendali oleh Gubernur, Terlaksananya penyebarluasan informasiGN-RHL, rapat-rapat koordinasi, terbitnya pedoman/petunjukpelaksanaan secara spesifik wilayah, terlaksananya pemantauan danbimbingan teknis ke lapangan, tersusunnya laporan kegiatan(semesteran dan tahunan) ke pusat.
c. Tim PembinaDi kabupaten dibentuk tim pembina yang secara langsung
diketuai oleh bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan GN-RHL di lapangan. Tim ini beranggotakan Dinas Teknis yangmengurusi kehutanan (Dinas Kehutanan), instansi terkait lainnya,Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, dan LSM. Tim ini bertugas untukmelaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, bimbinganteknis, pelaksanaan kegiatan fisik lapangan, pengawasan, danpengendalian serta melaporkan hasil pelaksanaan GN-RHL diwilayahnya. Dalam operasional sehari-hari, tim ini dibantu olehsekretariat. Output kerja tim ini antara lain adalah terbitnya SK timpengendali oleh Bupati, Terlaksananya penyebarluasan informasiGN-RHL, rapat-rapat koordinasi, terbitnya petunjuk teknis/manualkegiatan secara spesifik wilayah, terlaksananya pemantauan danbimbingan teknis ke lapangan, tersusunnya laporan kegiatan(semesteran dan tahunan) ke pusat.
d. Kelompok TaniAdanya kelompok tani sebagai pelaku GN-RHL menjadi
pembeda yang mendasar antara GN-RHL dengan kegiatan RHLsebelumnya. Kelompok tani ini bertanggungjawab atas pelaksanaanhutan rakyat, pembuatan bangunan konservasi tanah, dan rehabilitasihutan mangrove di lahan miliknya. Selain itu juga dapat bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan reboisasi. Outputkerja yang harus dipenuhi oleh kelompok tani ini adalah terbentuknyakelompok yang dilengkapi dengan susunan pengurus sertakelengkapan administrasi kelompok, tersusunnya rencana defenitif
REDD: Antitesis Reboisasi?
34 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kelompok dan rencana defenitif kebutuhan kelompok, tersusunnyakesepakatan kelompok dalam pelaksanaan GN-RHL, terlaksananyapengelolaan dana kegiatan, terlaksananya penyiapan lahan,terlaksananya distribusi bibit, terlaksananya penanaman danbangunan konservasi tanah, dan terbentuknya jaringan kerja antarakelompok dengan pemerintah, swasta, dan pihak terkait lainnyadalam penyediaan sarana produksi dan alih teknologi.
e. Pendamping Kelompok TaniAda dua sifat pendampingan terhadap kelompok tani pelaksana
GN-RHL. Yang pertama adalah pendampingan untuk penguatankelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha. Pendampingan inibisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tenagakerja sarjana terdidik, tenaga kerja sosial, organisasi pedulilingkungan seperti kelompok pencinta alam, kader konservasi alamdan organisasi lain yang dipandang mampu. Peran ini diberikankepada LSM dan kelompok-kelompok tersebut karena kelompok-kelompok tersebut dipandang sebagai lembaga non pemerintah yangmandiri serta bertujuan nyata untuk membantu pemerintah danmasyarakat.
Untuk menjalani peran tersebut, pendamping bertugas untukmengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilankelompok tani. LSM yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadipendamping harus terdaftar pada instansi yang berwenang, bergerakdalam bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan serta memahamiGN-RHL, memiliki tenaga pendamping yang terlatih danberpengalaman, memiliki peralatan yang diperlukan dan disetujuioleh kelompok tani. LSM yang memenuhi syarat-syarat ini diajukankepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pendamping GN-RHL diwilayahnya.
Pendampingan kedua adalah pendampingan yang bersifat teknispembuatan tanaman, pembersihan lahan, pembuatan lobang,pemasangan air, pemeliharaan bibit, penanaman, penyulaman, dan
REDD: Antitesis Reboisasi?
35Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
lain-lain. Pendampingan ini dilakukan oleh Penyuluh KehutananLapangan dan teknisi kehutanan lainnya.
f. BUMN, BUMS, dan KoperasiKelompok ini merupakan pelaku ekonomi yang diharapkan
berperan dalam GN-RHL melalui hubungan kemitraan yang sejajardan saling menguntungkan dengan kelompok tani, pemerintah danpemda, dalam suatu kerja sama yang berjangka panjang. Kerja samayang diharapkan terjalin antara BUMN, BUMS, dan koperasi adalahpenyediaan sarana produksi usaha yani, informasi dan akses pasar,bimbingan usaha produktif, bantuan permodalan, dan dukunganteknologi.
3) Perencanaan GN-RHLRencana Rehabilitasi hutan dan lahan disusun secara hirarkhis
atau berjenjang. Di tingkat nasional disusun Rencana UmumRehabilitasi Hutan dan Lahan yang berjangka waktu 15 tahun. Dalamskema perencanaan pemerintah, Rencana Umum RHL ini bisadisebut sebagai program jangka panjang rehabilitasi Hutan dan lahan.Setelah itu disusun Rencana Lima Tahunan Rehabilitasi Hutan danLahan sebagai program jangka menengah dan Rencana TahunanRehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai rencana jangka pendek.
A. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan LahanPola umum ini diatur di dalam Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK.20/Menhut-V/2001. Meskipun SK ini keluar sebelum GN-RHL dicanangkan, program GN-RHL menjadikan keputusan inisebagai dasar perumusan pola umum rehabilitasi hutan dan lahan.Pola Umum RHL ini berisi pendekatan dasar dalam fase prakondisidan fase aksi. Pendekatan yang digunakan adalah mencobamemaksimalkan dukungan dan komitmen politik serta meng-akomodasi tekanan global sebagai peluang. Dalam aspek kesatuanpengelolaan digunakan pendekatan ekosistem dalam kerangka
REDD: Antitesis Reboisasi?
36 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pengelolaan DAS dengan memperhatikan keanekaragaman jenis.Sedangkan dari segi aktor dan stakeholders digunakan pendekatancapacity building kelembagaan pemerintah, masyarakat, dankelembagaan ekonomi dan sosial budaya. Capacity building inibertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi, mening-katkan kesempatan ekonomi, kesesuaian sosial budaya dan teknologilokal, serta kepastian hukum penguasaan lahan untuk kelangsunganpenggunaan dan pengelolaannya (Pedoman Teknis GN-RHL).
Pola umum RHL ini juga menetapkan prinsip-prinsip yangdirasakan cukup memberikan harapan terhadap potensi keberhasilanGN-RHL. Beberapa prinsip yang secara politik dipandangmemperlihatkan kemajuan, terutama dalam memberikan porsi danposisi bagi peran serta masyarakat adalah prinsip menjadikan RHLsebagai bagian kebutuhan masyarakat dan prinsip memaksimalkaninisiatif masyarakat, teknologi lokal, dan kinerja manajemen yangakuntabel. Prinsip ini yang dicoba diterjemahkan dalam polapenyelenggaraan pada fase aksi dengan memaksimumkan inisiatifmasyarakat, teknologi lokal dalam manajemen rehabilitasi. Namunpada pola relasi ini, pengingkaran terhadap prinsip ini sudah mulaikelihatan dengan menerapkan pola yang lebih mengutamakan hasildari pada proses. Pengutamaan pada hasil akan bisa memperkecilruang partisipasi masyarakat.
B. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 5 TahunanRencana ini disusun oleh daerah berdasarkan kerusakan hutan
dan lahan di wilayah kerja BP DAS, yang secara indikatif menjadiprioritas untuk direhabilitasi selama 5 (lima) tahun. Rencana RHL5 tahunan ini merupakan rencana teknis semi detail yang disusunberdasarkan unit DAS di seluruh wilayah kerja BPDAS dengankedalaman analisis tingkat Sub DAS. Rencana RHL 5 tahunan iniberisi :a. Sasaran lokasi kegiatan RHL yang bisa dilakukan di dalam dan
di luar kawasan hutan negara. Sasaran lokasi dalam kawasan
REDD: Antitesis Reboisasi?
37Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
hutan negara adalah hutan konservasi, hutan lindung yangterdeforestasi, dan hutan produksi yang tanahnya miskin (kritis)yang tidak dibebani hak atau tidak dicadangkan untukpembangunan hutan tanaman. Sedangkan yang di luar kawasanhutan bisa dilakukan pada lahan milik;
b. Sasaran Areal RHL, yang ditentukan menurut kriteria:Urutan prioritas DAS/Sub DAS yang ditentukan menuruttingkat kekritisan sebagaimana ditetapkan dalam SK MenhutNo. 284/KPTS-II/2009;Hasil indikatif rehabilitasi hutan dan lahan yang diinterpretasidari citra satelit dan data lahan kritis yang diverifikasi denganpengecekan lapangan;Kerawanan bencana yang diindikasikan dari frekuensi banjir,tanah longsor, dan kekeringan di wilayah DAS pada 3 tahunterakhir, terjadinya tsunami atau abrasi air laut di daerah pantaiyang nyata atau potensial menimbulkan bencana bagi manusia;Perlindungan bangunan vital di DAS untuk kehidupanmasyarakat.
c. Pertimbangan teknis manajerial, yang antara lain harusmemperhatikan aspek kesiapan kelembagaan daerah danmasyarakat, komitmen daerah, sumber daya lain yang tersediaserta pertimbangan khusus bagi daerah yang masih bersengketa;
d. Metode perencanaan dilakukan dengan cara penginderaan jarakjauh dengan teknik analisis spatial, dengan menginterpretasikancitra satelit dan peta dasar, overlay peta-peta tematik, danadministratif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisisdata-data kualitatif dan numerik. Survey lapangan dilakukanuntuk memperoleh akurasi data lapangan;
e. Mekanisme perencanaan dilakukan secara terpadu yangmelibatkan BP DAS, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota daninstansi terkait;
f. Spesifikasi rencana, yang disusun menurut fungsi kawasan hutan
REDD: Antitesis Reboisasi?
38 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
negara dan di luar kawasan hutan negara sesuai dengan fungsikawasannya dan unit pengelola arealnya, yang dijabarkan menurutwilayah sasaran, sasaran indikatif luas RHL (total sasaran, sasaran5 tahun dan proyeksi tahunan) yang dipetakan dalam skala 1:5000s/d 1:100.000.
C. Rencana Teknis Tahunan (RTT)RTT ini merupakan rencana fisik semi detail dalam pembuatan
tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan dan bangunankonservasi tanah setiap tahun pada satu atau lebih DAS dalamwilayah kabupaten/kota. Dalam RTT ini berisi tentang letak kegiatanRHL dalam wilayah kabupaten/kota, DAS/Sub DAS, luas lahankritis, lokasi, dan volume kegiatan menurut fungsi kawasan hutandan pola penyelenggaraan, jenis kegiatan, kondisi fisik lapangan,pola perlakuan, sarana prasarana, jenis tanaman, dan jumlah bibitper kegiatan. Tanggung jawab penyusunan RTT ini berada di DinasKehutanan Kabupaten/Kota. Rencana Teknik RHL 5 tahunandigunakan sebagai acuan yang digambarkan dalam peta rencanadengan skala 1:25.000. Rancangannya disiapkan oleh Sub DinasPerencanaan atau program untuk disetujui oleh Kepala DinasKehutanan. Seterusnya disampaikan kepada Kepala BP DAS yangselanjutnya akan melakukan pencermatan/pemantapan bersama olehBP DAS dan instansi penyusun. Jika disepakati, BP DAS membuatrekap dan menandatanganinya bersama Kepala Dinas Kehutanan.
D. Rencana Teknis KegiatanRancangan ini berisi tentang rancangan kegiatan untuk setiap
jenis kegiatan. Misalnya rancangan teknis kegiatan pembuatantanaman reboisasi hutan lindung dan hutan produksi, rehabilitasihutan mangrove, hutan rakyat, hutan kota, turus jalan, dan bangunankonservasi tanah. Rancangan kegiatan ini berisi rancangan fisik danrancangan biaya. Rancangan ini dituangkan ke dalam buku rancangandan dilampiri dengan peta rancangan dan peta situasi. Rancangan
REDD: Antitesis Reboisasi?
39Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
teknis kegiatan ini sudah sangat mikro pada tingkat penggambaranlokasi (propinsi, kabupaten/kota/kecamatan/KPH/RPH, desa/kelurahan, DAS, register kawasan hutan, status kawasan, blok, petak,dan anak petak). Rencana teknis kegiatan ini juga sudah sangat detailmencantumkan uraian kegiatan mulai dari jenis kegiatan, risalahfisik lapangan, target luas, cara pembuatan, jumlah dan jenistanaman/bangunan, bahan dan peralatan kerja, tenaga kerja danjadwal waktu. Juga sudah memuat situasi lapangan berupa batasluar dan batas petak, bangunan alam, tata letak tanaman, jalan masuk,dan lain-lain sesuai kondisi lapangan. Sedangkan rancangan biayamemuat uraian rinci kebutuhan biaya per jenis pekerjaan dan jumlahbiaya keseluruhan.
4). Waktu dan Tahapan Penyusunan RancanganRancangan disusun pada tahun sebelum pelaksanaan. Biasanya
diistilahkan dengan T-1, tetapi diberi juga kemungkinan untukmenyusunnya pada tahun berjalan atau T-0. tahapan penyusunanrancangannya sebagai berikut :
a) Orientasi lapangan;b) Penyiapan bahan dan rencana kerja;c) Pengumpulan data bio fisik melalui pengamatan dan
pengukuran lapangan;d) Pengumpulan data sosial ekonomi melalui wawancara dan
data sekunder;e) Pengolahan dan analisa data;f) Pengukuran kembali dan pemasangan patok batas;g) Penyusunan nazca;h) Penyusunan peta rancangan dan gambar rancangan.
5) Pelaksanaan GN-RHLAda dua pola pelaksanaan GN-RHL. Pola pertama adalah
pelaksanaan secara swakelola di mana kegiatan ini dilakukanlangsung oleh instansi pemerintahan di daerah. Dalam hal ini adalah
REDD: Antitesis Reboisasi?
40 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Dinas Kehutanan. Pola ini berlangsung mulai tahun 2003 – 2006.Rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan pola ini dapat dilakukandi dalam dan di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan dikenaldengan kegiatan reboisasi yang bisa dilakukan di kawasan lindung,konservasi, dan produksi. Di luar kawasan hutan dilakukan programpenghijauan melalui pembuatan hutan rakyat. Pembuatan hutanrakyat ini dilakukan dengan membentuk kelompok tani yangmempunyai lahan dengan luas minimal 25 ha. Pada pola ini adajaminan kelompok tani yang menanam dijamin akan menjadi pihakyang berhak memanen hasil dari hutan rakyat tersebut. Lokasipembangunan hutan rakyat ini dapat dilakukan pada tanah milikrakyat dan tanah adat yang kurang cocok untuk pertanian tanamanpangan, sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan untukdikembangkan menjadi hutan rakyat. Lokasi terletak pada bagianhulu sungai dan perlu dihutankan, baik karena sudah kritis maupunkarena dibutuhkan pengayaan atas tanaman yang sudah ada. Tahapan
REDD: Antitesis Reboisasi?
41Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat Teluk Meranti pada Juli2010 lalu di area hutan yang sudah rusak akibat perambahan liar.sumber : scale up
pelaksanaan pembangunan hutan rakyat ini dimulai denganprakondisi melalui sosialisasi yang ditindaklanjuti denganpembentukan kelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha.Selanjutnya kegiatan didasarkan pada rencana teknis kegiatan.
Pola kedua adalah pola kerjasama dengan pihak ketiga melaluikontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. Jikapada pola pertama yang swakelola, kegiatannya tersebar di dalamdan di luar kawasan hutan, sehingga memungkinkan dilakukanpenghijauan melalui pengembangan hutan rakyat, pola kontrakkerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dikhususkandilakukan di dalam kawasan hutan. Artinya kegiatan yang dilakukanadalah kegitan reboisasi baik pada hutan lindung, hutan konservasi,maupun hutan produksi. Pola ini dikenal juga dengan pola tahunjamak atau multiyears.
Jika dilihat dari segi keterlibatan masyarakat, pola ini sebenarnyatidak terlalu berbeda dengan pola swakelola untuk kegiatan reboisasi.Karena posisi kelompok masyarakat hanyalah sebagai pekerja padabeberapa jenis pekerjaan seperti membuat lobang, menanam,memelihara, dan lain-lain. Masyarakat tidak akan bisa menjadipemanfaat langsung dari tanaman reboisasi karena berlokasi di dalamkawasan hutan yang memang tidak diizinkan untuk memanfaatkankayunya. Pemanfaatan hanya bisa untuk hasil hutan bukan kayupada kawasan hutan yang berfungsi lindung, itupun juga harusberdasarkan izin dari pemerintah.
Pola pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadanhukum ini dimulai pada tahun 2007. Penerapan pola ini didasarkanpada Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2007. Dari penelusurandokumen, tidak ditemukan alasan yang secara eksplisit disebutkansebagai penyebab perubahan pola swakelola menjadi pola pelaksananberdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga. Namun secaraimplisit, bisa dibaca alasan perubahan ini didasarkan pada keadaandimana pembuatan tanaman reboisasi harus dilaksanakan secaraberkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, baik penyediaan bibit,
REDD: Antitesis Reboisasi?
42 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
penanaman, dan pemeliharaannya sehingga secara teknis tanamandapat tumbuh sehat dan kuat serta mampu beradaptasi dengan alamsekitarnya : (Lampiran Permenhut No. P.22/Menhut-V/2007, hal24). Alasan atau argumentasi ini dinilai cukup substantif untuktujuan diperolehnya komitmen dan kepastian dukungan pendanaandari APBN dalam tahun jamak. Tetapi alasan ini sebenarnya tidakcukup argumentatif untuk membenarkan perubahan pola menjadikontrak kerja kepada pihak ketiga. Karena aspek keberlanjutan dalamkurun waktu yang lebih panjang sebenarnya tetap bisa dipenuhimelalui pola pelaksanaan berdasarkan swakelola.
Menurut Tri Handoyo (BPDAS Agam Kuantan) alasan pemilihanpola pelaksanaan melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga tersebutlebih disebabkan karena tanggungjawab atas kawasan hutan yangberada pada pemerintah pusat. Keterbatasan SDM di kabupaten/kota dibandingkan dengan luas dan jarak kawasan hutan yangmenjadi lokasi GN-RHL dan keterbatasan sumber tenaga kerja.Beberapa alasan ini sesungguhnya tetap terasa tidak logis, karenatanggungjawab pemerintah pusat bisa dilakukan oleh pemerintahandi daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, sebagaimana polaswakelola. Keterbatasan sumber tenaga kerja juga masih sangat bisadiperdebatkan, mengingat perusahaan penerima kontrak juga akanmerekrut tenaga kerja. Karena itu sangat mungkin ada alasan lainyang tidak diungkapkan, misalnya persoalan-persoalan seputarkelemahan kemampuan kelembagaan instansi teknis di daerah,karena beban-beban birokrasi yang dipikulnya.
Sebenarnya Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2007 sama sekalitidak menghapuskan pola swakelola. Pola kontrak kerjasamadengan pihak ketiga hanya dilakukan terhadap kegiatan pembuatantanaman di dalam kawasan hutan yang dibiayai dengan APBN danAPBD. Pelaksanaan dengan pola swakelola sebenarnya masihdimungkinkan. Misalnya pembuatan tanaman dalam kawasan hutantertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dilakukandengan swakelola melalui operasi bakti TNI (pasal 12 ayat 3).
REDD: Antitesis Reboisasi?
43Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Pembuatan tanaman di luar kawasan hutan yang dibiayai denganAPBN dan APBD dilaksanakan dengan swakelola melalui suratperjanjian kerjasama dengan kelompok tani (Pasal 12 ayat 4). Namunsepertinya setelah keluarnya Perpres ini, kegiatan GN-RHLumumnya dilakukan di dalam kawasan hutan secara kontraktualdengan pihak ketiga. Setidaknya gambaran ini terlihat di SumateraBarat, di mana sejak tahun 2007 tidak ada lagi kegiatan pembuatanhutan rakyat yang dikelola oleh kelompok tani. Alasan yangdikemukakan baik oleh BP DAS maupun oleh Dinas Kehutanan,ketentuan yang ada adalah kegiatan GN-RHL hanya dilakukan didalam kawasan hutan saja. Padahal Perpres yang dimaksud sebagaiketentuan tersebut, sesungguhnya masih memberi ruang. Dalamkonteks ini sebenarnya menarik untuk menelusuri lebih lanjutmengapa Perpres tersebut diterapkan terbatas untuk melakukankegiatan GN-RHL di dalam kawasan hutan dengan pola yangkontraktual. Mengapa ketentuan dalam pasal 12 ayat (4) terkaitdengan pembuatan hutan rakyat melalui kerjasama dengan kelompoktani tidak dilaksanakan.
6). Target RHL pada GN-RHLSepanjang kurun waktu 5 tahun pertama GN-RHL (2003 – 2007)
direncanakan akan merehabilitasi hutan dan lahan seluas 3 juta ha.Jumlah luasan ini akan dicapai secara bertahap. Pada tahun 2003ditargetkan merehabilitasi 300.000 ha. Pada tahun 2004 ditargetkanmerehabilitasi 500.000 ha. Pada tahun 2005 ditargetkanmerehabilitasi 600.000 ha. Pada tahun 2006 ditargetkanmerehabilitasi 700.000 ha, dan 900.000 ha pada tahun 2007. Untuktarget tahun 2008 dan 2009 tidak berhasil ditemukan. Tapi jikamenggunakan penambahan target tiap tahun sampai tahun 2007,sampai tahun 2009 sepertinya target rehabilitasi tidak akan melebihiluasan 1,5 juta ha.
Jika dibandingkan dengan laju angka kerusakan hutan yangberkisar antara 1,6 – 2 juta ha pertahun, target rehabilitasi ini terasa
REDD: Antitesis Reboisasi?
44 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
sangat jauh dari cukup. Sebab dengan hanya mengambil angka lajukerusakan hutan pertahun 1,6 juta ha, dan angka tersebut konstansampai pada tahun 2009, maka dari tahun 2003 - 2009 luasan hutandan lahan yang rusak sudah bertambah sebanyak 9,6 juta ha. Artinyatotal lahan kritis sudah akan melampaui angka 100 juta ha. Melaluiprogram GN-RHL luasan lahan kritis ini hanya akan bisa dikurangi1,5 juta ha. Itupun dengan mengasumsikan seluruh target tersebutberhasil direalisasikan secara keseluruhan. Jumlah yang tentunyasangat tidak signifikan.
5. Politik Hukum Pengelolaan Hutan di IndonesiaBila dipahami secara normatif, kehutanan sebagaimana dimaksud
UU No. 41/1999, dipahami sebagai sebuah sistem pengurusan yangbersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yangdiselenggarakan secara terpadu (pasal 1 butir 1). Dengan demikianpengelolaan kehutanan di Indonesia dapat diartikan sebagai segalakebijaksanaan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintahIndonesia berkenaan dengan sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Konstitusi dasar negara ini, UUD 1945, sesungguhnya telahmenggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam denganprinsip yang sangat ideal. Pada pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwabumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya dalam pengaturan danpelaksanaan selanjutnya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspekmenguasai oleh negaranya sehingga mengedepanlah konsep HakMenguasai Negara (HMN). Konsep ini dapat kita temui diantaranyadalam UU No. 5/1960 tentang Agraria (UUPA) dan lebih khususmenyangkut kehutanan dalam UU No. 5/1967 tentang Kehutanan.
Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa Hak MenguasaiNegara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakanperuntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air
REDD: Antitesis Reboisasi?
45Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruangangkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumantara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi,air dan ruang angkasa. Ketentuan mengenai Hak Menguasai Negarajuga dimuat dalam UU No. 5/1967 tentang Kehutanan. Pasal 5UU tersebut menegaskan bahwa semua hutan dalam wilayahRepublik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara. Hak Menguasai Negara tersebutmemberi wewenang pemerintah untuk:a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan
dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalammemberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.Sejak UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan
dibuat dan diterapkan hingga kini, kesempatan atau peluangmasyarakat—khususnya yang berada di dalam dan di sekitar hutan—untuk berperan serta mengelola dan mendapat manfaat dari hutansangatlah terbatas. Ketiadaan kesempatan tersebut, dapat kita lihat,selain di dalam UU No. 5/ 1967, juga dari sejumlah peraturanpemerintah turunannya seperti PP No. 21/1970 tentang HPH danHPHH, PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan dan PP No.28/1985 tentang Perlindungan Hutan (Sembiring, 2003).
Hal ini menyebabkan praktek pengelolaan hutan sangatdidominasi oleh negara. Negara berwenang penuh menetapkankriteria dan mendefinisikan kepentingan nasional yang dimaksuddalam UU. Akibatnya, sumber daya alam hutan dengan legitimasiperaturan pelaksana lanjutan lebih didominasi segelintir orang yangmemiliki akses dalam menentukan kebijakan. Pada sisi lain,menyebabkan peminggiran masyarakat-masyarakat (adat) dari
REDD: Antitesis Reboisasi?
46 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pengelolaan hutan yang berakibat pada pemiskinan struktural dantidak meratanya kemakmuran pada masyarakat.
Di awal berkuasanya Rezim Orde Baru, pemerintah sangatberambisi untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan memacupertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber kekayaan negara padawaktu itu yang siap digarap adalah sumber daya alam, khususnyasektor kehutanan, terutama pemanfaatan kayu untuk mendatangkandevisa negara sebesar-besarnya. Dari tahun 1969 sampai 1974pendapatan negara dari kayu meningkat sebesar 2800%, terutamadari areal konsesi seluas 11 juta ha di Kalimantan Timur (Christantydan Atje 2000). Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesiaberkomitmen untuk menerapkan pedoman International TropicalTimber Organization (ITTO) mengenai pengelolaan hutan yangberkelanjutan sebelum tahun 2000 (Seve 1999). Dalam RencanaPembangunan Lima Tahun yang keenam, pemerintah lebihmenekankan pada upaya pelaksanaan pengelolaan hutan yangberkelanjutan.
Berhubung eksploitasi hutan membutuhkan modal besar, makadiciptakanlah iklim yang mendukung bagi masuknya modal (Saman,dkk, 1992). Maka lahirlah UU No 1/1967 tentang Penanaman ModalAsing (PMA), UU No. 5/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 7/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Inilahawal dimulainya bencana berkepanjangan bagi sumber daya alamkhususnya hutan. Keluarnya berbagai izin HPH, HPHTI, IPK sertakonversi untuk perkebunan dan bentuk-bentuk perizinan lainnyatelah mengakibatkan deforestasi hutan secara terus menerus danmenimbulkan bencana berkelanjutan.
Pola perumusan kebijakan yang berorientasi eksploitatif dengankuatnya dominasi negara membuat kebijakan tersebut sangatsentralistik, top down dan minim sekali partisipasi masyarakat. Posisimasyarakat lebih dipandang sebagai obyek dalam perumusankebijakan ketimbang dianggap sebagai subyek yang mestinya ikutserta menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya
REDD: Antitesis Reboisasi?
47Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
lingkungan hidup. Pada bagian lain kebijakan-kebijakan yangdikeluarkan menjadi sektoral dan tidak terintegrasi secara baik.Masing-masing sektor dianggap sebagai bagian tersendiri yang dapatdipisahkan pengaturannya antara satu dengan yang lain. Misalnya,masalah hutan diatur sendiri, terpisah dengan masalah tambang.Meski sudah ada UU Pokok Agraria (UUPA) yang bisa menjadipayung pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secarakeseluruhan, tetapi yang justru ter jadi adalah munculnyapertentangan antar UU. Misalnya dalam UUPA hak masyarakatadat diakui tetapi dalam UU Kehutanan (UU No.5/1967) hakmasyarakat adat dalam pengelolaan hutan tidak diakui. Ataumisalnya pada UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup, disebutkan bahwa menerapkan prinsip keberlanjutan adalahsyarat penting dalam pengelolaan lingkungan tetapi faktanya hutanmengalami kerusakan parah karena eksploitasi besar-besaran akibatpemberlakuan UU Penanaman Modal dan UU Kehutanan.
Selama orde baru sesungguhnya pihak departemen kehutananbelum melakukan pengelolaan hutan, sebab yang mengusahakannyaadalah para pengusaha. Pada masa itu pengusaha hanya menjadialat bagi kepentingan kekuasaan. Era ini sudah harus ditinggalkanjika ingin pengelolaan hutan lebih baik dan mendapat legitimasipublik. Konflik hutan dan tambang yang sangat marak akhir-akhirini masih mencerminkan pemikiran modernitas pembangunan yangsangat berpihak pada penanaman modal asing dengan mengor-bankan kepentingan lingkungan dan konservasi. Hedonisme politikpemerintah seperti ini tidak boleh lagi terjadi di lingkungan sumberdaya hutan, oleh karena itu pemerhati dan pelaku pengelola sumberdaya hutan harus menolak pendekatan tersebut.
Setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru, ciri kebijakan yangeksploitatif tidak serta merta hilang. Bahkan pada masa pemerintahanPresiden Abdurahman Wahid yang dianggap lahir dari proses palingdemokratis pun belum menampakkan niat untuk mendemokratiskanpengelolaan sumber daya alam lingkungan. Tak cukup hanya wilayah
REDD: Antitesis Reboisasi?
48 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
daratan, wilayah laut pun menjadi sasaran eksploitasi. Salah satubentuk konkrit adalah dengan dibentuknya Kementerian EksploitasiKelautan. Polemik yang berkembang terkait kebijakan kementerianbidang tersebut adalah ketika itu adalah pemerintah berencanamenyewakan pulau-pulau kecil kepada investor asing (Fauzi dkk,2002).
Contoh lain adalah keluarnya Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang (Perpu) No. 1/ 2004 tentang Perubahan UUNo.41/1999 tentang Kehutanan. Perpu yang dikeluarkan pada masaPemerintahan Megawati ini pada prinsipnya menambah ketentuanbaru pada UU No. 41/1999 pasal 83 (a) dan pasal 83 (b). Pasal 83(a) menegaskan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidangpertambangan di kawasan sebelum berlakunya UU No 41/1999tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnyaizin atau perjanjian tersebut (Kompas, 12/3/2004). Perpu inimenggambarkan sikap pemerintah atas tarik menarik antarakepentingan ekonomis-eksploitatif hutan dengan konservasi hutan.Jelas terlihat pemerintah berpihak pada kepentingan ekonomis –eksploitatif. Kalangan konservasionis pun langsung menyatakansikap penyesalan bahkan protes terhadap keluarnya Perpu tersebut,antaranya dilakukan Walhi, Jatam, dan Greenomic. Bahkan, setelahmenjadi UU pun Perpu ini tetap digugat kalangan organisasi nonpemerintah ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
Pada era reformasi, banyak kalangan menganggap lahirnya UUNo. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah akan menjadi landasankuat bagi desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam UU tersebutditegaskan bahwa pengaturan kewenangan yang lebih dominanberada di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah (pusat) hanyamenyangkut lima aspek yaitu di bidang politik luar negeri, pertahanankeamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Selebihnyamenjadi kewenangan daerah. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwadaerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian
REDD: Antitesis Reboisasi?
49Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Namun dalam perjalanannya, UU ini dianggap terlalu berlebihan
karena memicu timbulnya arogansi daerah. Maka kemudian lahirlahketentuan lain yang tidak sejalan dengan UU ini seperti PeraturanPemerintah (PP) No. 34/2002. Selain dinilai tidak transparan dalampenyusunannya, substansi PP ini dianggap bertentangan denganprinsip otonomi daerah bahkan dengan UU Kehutanan sendiri.Semangat yang dibawa oleh PP ini adalah eksploitasi, pengam-bilalihan kewenangan daerah khususnya untuk masalah perizinan,serta biaya ekonomi tinggi. Apalagi UU No. 41/ 1999 masihmenegaskan tentang dominasi pemerintah (pusat) dalam bidangKehutanan. Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa semua hutandi dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintahuntuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan denganhutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayahtertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; mengaturdan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang denganhutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenaikehutanan.
Bahwa tujuan penguasaan itu untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat atau dapat dikuasakan kepada daerah ataumasyarakat adat, tetap saja ditegaskan dengan kalimat “sekedardiperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”Tampaknya agar tetap dianggap konsisten dengan UU Kehutanan,Departemen Kehutanan juga mengeluarkan berbagai keputusan yangmencabut kewenangan daerah dengan mengeluarkan izinpengelolaan hutan (HPH skala kecil ataupun IPK) baik sementaramaupun permanen. Hal ini kemudian menimbulkan tarik menarikkewenangan yang tak kunjung selesai sampai sekarang. UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pun akhirnya direvisi menjadi
REDD: Antitesis Reboisasi?
50 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
UU No 32/2004.Undang-undang pemerintahan yang baru (UU No 32/2004)
secara umum tidak menegaskan bahwa masalah pengelolaan hutanmenjadi kewenangan pemerintahan daerah, meski tetap menyatakanbahwa yang menjadi kewenangan pemerintahan (pusat) masih samadengan ketentuan UU sebelumnya. Urusan pemerintahan pusatmeliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneterdan fiskal nasional, dan agama (Pasal 10 ayat 3 UU No. 32/2004).Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecualiurusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengantujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum,dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menye-lenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan denganpemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungantersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
Pasal-pasal UU No. 32/2004 tidak menyebutkan secara tegasbahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan menjadikewenangan pemerintah daerah, akan tetapi lebih menegaskanadanya keterkaitan antara sesama pemerintah daerah dan propinsidengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam.Bagaimana keterkaitannya akan sangat bergantung kepada aturanyang disyaratkan oleh UU ini mengenai aturan lebih lanjut tentangpengelolaan sumber daya alam (Pasal 17).
Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa di tengah kentalnyasemangat eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan, porsikewenangan pengelolaan hutan antara pemerintahan pusat dandaerah sampai saat ini belum jelas. Tetapi satu hal yang pasti, baikpemerintah pusat maupun daerah sama-sama berorientasieksploitatif terhadap sumber daya hutan. Namun semenjak era
REDD: Antitesis Reboisasi?
51Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
reformasi ada upaya membangun keseimbangan antara kebijakan-kebijakan berorientasi eksploitasi sumber daya hutan, dan kebijakan-kebijakan bersifat konservasi (penyelamatan) sumber daya hutan.Era reformasi juga menggeser fokus pengelolaan hutan denganberusaha mencari keseimbangan yang lebih baik antara pengelolaanhutan berbasis masyarakat dan berbasis negara. Hal ini sedikit banyaktidak terlepas dari peran Dana Moneter Internasional (IMF)memaksakan pergeseran paradigma pengelolaan hutan ini kepadaPemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan sektorkehutanan pada awal tahun 1998 di bawah Memorandum on Economicand Financial Policies (MEFP) yang ditandatangani oleh PemerintahIndonesia dan IMF (Seve 1999). Akan tetapi, perubahan yangdiajukan tidak mencakup persoalan yang mendasar dan kom-prehensif karena fokus MEFP hanya pada Dana Reboisasi (DR),pembatasan perdagangan, provisi sumber daya hutan, privatisasi,pelelangan, jangka waktu dan peralihan konsesi, konversi lahan, dandana jaminan kinerja (Seve 1999).
Pergeseran dari pengelolaan hutan yang berbasis perusahaanswasta dan berskala besar menjadi pengelolaan hutan berbasismasyarakat yang berskala lebih kecil, juga tercermin dalam kegiatanrehabilitasi. Dua usaha rehabilitasi yang dimulai oleh pemerintahbaru-baru ini dirancang berdasarkan paradigma baru tersebut.Pendekatan utama yang menggunakan payung hutan kemasya-rakatan/perhutanan sosial dilakukan untuk menerapkan programpokok, seperti GN-RHL/Gerhan yang diluncurkan pada akhir tahun2003 serta program Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 di bawah koordinasipemerintah kabupaten.
Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan RencanaPembangunan 25 tahun, yang dibagi dalam lima tahap berdasarkanRencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejalan dengan itu,program rehabilitasi hutan juga diterapkan mengikuti cara yang sama.Pada saat itu, program biasanya dilaksanakan pada tingkat proyek
REDD: Antitesis Reboisasi?
52 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Setelah keputusan yangdiambil dalam Kongres Kehutanan Pertama pada tahun 1955,pemerintah membagi usaha rehabilitasi ke dalam dua kategori yaitu:kegiatan rehabilitasi yang difokuskan pada kawasan hutan negarayang dulunya berhutan disebut reboisasi, dan kegiatan rehabilitasiyang difokuskan pada lahan masyarakat (di luar kawasan hutannegara) yang tidak berhutan disebut penghijauan (Mursidin et al.1997).
Secara umum, kebijakan rehabilitasi hutan menggunakanpendekatan top-down dari tahun 1950-an hingga 1970-an, yangkemudian pada akhir tahun 1990-an secara konseptual berubahmenjadi lebih partisipatif. Antara tahun 1980-an hingga pertengahantahun 1990-an, kegiatan rehabilitasi berada dalam masa transisi.Perubahan dalam beberapa aspek kebijakan sejak Reformasi tahun1998 telah mempengaruhi pendekatan pemerintah dalam
REDD: Antitesis Reboisasi?
53Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Deforestasi yang terjadi terhadap hutan alam di lingkungan wilayah TelukMeranti, mendorong masyarakat tempatan untuk peduli, sehingga memicumunculnya inisiatif penanaman 9000 pohon yang dilakukan pada Juli 2010yang lalu. sumber : scale up
menetapkan kebijakan rehabilitasi menuju pada partisipasimasyarakat yang relatif lebih besar dalam pelaksanaan program-program rehabilitasi.
Namun penting dicatat, selama periode partisipatif, walaupunketerlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi masihterbatas, para penanam pohon berada pada posisi yang lebih baikdan terlibat dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan.Mereka juga berhak mendapatkan hasil dari kegiatan rehabilitasi.Peran lebih besar dimungkinkan untuk masyarakat karena sistembirokrasi mengalami transformasi struktural, sehingga peranpemerintah pusat sekarang kurang menonjol dibandingkan denganperan pemerintah kabupaten. Meski demikian, peran masyarakatsetempat masih lemah dibandingkan dengan peran pemerintahdaerah (di tingkat propinsi atau kabupaten). Walau istilah‘perencanaan partisipatif ’ telah digunakan selama periode partisipatif,dalam kenyataannya rencana masih lebih banyak dirancang denganmenggunakan pendekatan otoriter daripada pendekatan partisipatif.
REDD: Antitesis Reboisasi?
54 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Bagian Ketiga
• Kebijakan Penghutanan danImplementasinya di Tiga Lokasi
di Tiga Propinsi di Sumatera
3.1. KONTESTASI ARUS DEFORESTASI DANREFORESTASI: STUDI KASUS POLITIKHUKUM PENGELOLAAN KAWASAN SUAKAMARGASATWA RIMBANG BALING,PROPINSI RIAU
3.1.1. KEBIJAKAN DI BIDANG KEHUTANANPROPINSI DI RIAU
Era reformasi memberi ruang kepada daerah untuk mengeloladirinya sendiri dengan wilayah otoritas yang melebihi era sebelumreformasi. Penerbitan UU N0 22 Tahun 1999 menjadi penanda ataspelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalammengelola sumber daya alam di daerahnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, daerah mempunyai hak untuk menetapkankebijakan daerahnya sendiri secara otonom. Sementara itupemerintah propinsi pada praktiknya masih lebih banyak berfungsisebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
1. Potret Deforestasi dan Degradasi Hutan RiauDeforestasi dimaknai sebagai hilangnya atau terdegradasinya
habitat hutan yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia (Cifor,2008:18). Peristiwa-peristiwa alam yang mengakibatkan deforestasiantara lain seperti tingginya curah hujan yang pada gilirannyamengakibatkan tanah rentan terhadap longsor dan erosi. Namunsangat sulit untuk memperkirakan total wilayah hutan yangterdegradasi karena bencana alam. Kejadian terakhir yang dapatdigunakan untuk menjelaskan contoh bencana alam yangmenyebabkan degradasi hutan adalah peristiwa banjir bandangSungai Bahorok di Sumatera Utara pada November 2003.
REDD: Antitesis Reboisasi?
57Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Di Riau belum ditemukan peristiwa alam seperti banjir bandangyang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan. Justru sebaliknya,konversi hutan yang telah mengakibatkan terjadinya banjir di banyaktempat di propinsi ini. Karena itu, faktor pendorong terjadinyadegradasi hutan di Riau lebih banyak dikarenakan faktor manusia.Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan hutanmerupakan penyebab utama deforestasi, seperti misalnya operasipengusahaan hutan, penebangan liar, dan pembangunan perkebunanyang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.
Grafik 1. Peruntukan Kawasan di Propinsi Riau
WWF (2008:14-16) mencatat bahwa antara tahun 1982-2007,Riau telah kehilangan seluas 4.166.381 ha (65%) dari tutupan hutanasli, yaitu berkurang dari 4.420.499 ha (78% luas daratan utamaRiau) menjadi 2.254.118 ha (27%). Kawasan-kawasan hutan tersebutjuga terfragmentasi menjadi delapan blok utama yang terpisah-pisaholeh industri perkebunan kelapa sawit dan HTI serta lahan terlantar.Tanah gambut Riau telah kehilangan 57% (1.831.193 ha dari hutan-hutannya); sementara tanah non gambutnya kehilangan 73%(2.335.189 ha) dari hutan-hutannya.
REDD: Antitesis Reboisasi?
58 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Gambar 1. Perbandingan Peta TutupanHutan Riau pada 1982 dan 2007
Sumber : WWF Riau, 2008:16
Grafik 2. Tutupan hutan di atas tanah gambut dan non gambutdi dalam daratan utama Propinsi Riau kurun waktu 1982-2007
Sumber : WWF Riau, 2008:14
REDD: Antitesis Reboisasi?
59Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi disebuah harian Kompas terbitan pertengahan April 2010, (http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10) menyatakan bahwa selamakurun waktu 2000-2009, pembukaan hutan di Propinsi Riaumencapai 1,06 juta ha. Greenomics Indonesia menyatakan,pembukaan hutan itu sebagai deforestasi dan 73,45 persen diantaranya justru disebabkan kebijakan pemerintah atau faktormanusia. Sebanyak 73,45 persen atau sekitar 776.000 ha hutan diRiau selama kurun waktu tersebut dibuka untuk Hutan TanamanIndustri, pembukaan areal hak pengusahaan hutan, dan pembukaanhutan untuk perkebunan kelapa sawit. Sementara sebanyak 26,55persen atau sekitar 280.000 ha lahan di Riau terdegradasi akibatadanya illegal logging. Menurut Effendi, dari total 776.000 ha hutanRiau yang terdegradasi, sebanyak 414.900 ha dikarenakan pemberianizin untuk Hutan Tanaman Industri.
Data Greenomics menarik dibahas, karena mengategorisasikanperubahan tutupan hutan alam akibat pemberian izin HTI sebagaikawasan hutan yang terdegradasi. Dikatakan menarik setidaknya karenacara pandang ini berlawanan dengan sikap resmi negara yang tetapmengelompokkan kawasan hutan yang telah dibebani izin HTI sebagaikawasan hutan, bukan hutan yang terdegradasi. Agaknya, pe-ngategoriasasian Greenomics ini dilatari pandangan bahwa perubahanfungsi ekologis dan budaya masyarakat di sekitar hutan akibat perubahanstatus dari hutan alam menjadi kawasan HTI ini yang menjadi alasandikelompokkannya areal HTI sebagai kawasan hutan yang terdegradasi.Memang sulit disangkal bahwa areal hutan yang dibebani izin HTIterut mengalami perubahan fungsi ekologis maupun kebudayaan biladibandingkan dengan ketika masih menjadi hutan alam.
2. Kebijakan-kebijakan Perlindungan HutanSejalan dengan kebijakan perlindungan hutan di Indonesia, politik
perlindungan hutan di Riau sedikitnya dapat dipilahkan ke dalam
REDD: Antitesis Reboisasi?
60 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dua kelompok, pertama penetapan kawasan hutan sebagai hutanlindung, dan kedua melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang telahterdegradasi.
Total kawasan lindung di Propinsi ini adalah 1.853.548 ha, denganperincian kawasan lindung 448.357 ha; kawasan lindung gambut882.243 ha; cagar alam 522.948 ha. Rehabilitasi hutan dan lahantahun 2003 adalah sebanyak 21.906 ha, terdiri dari 16.765 hareboisasi di kawasan lindung dan 5.141 ha penghijauan di hutanrakyat. Sementara, pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkanizin pemanfaatan kayu di lahan seluas 51.716 ha. Kalau dilihatpraktik rehabilitasi pada tahun yang sama (2003), terungkap bahwahanya 2.090 ha yang direhabilitasi. Tahun 2004, rencana kegiatandi lahan seluas 16.105 ha di enam kabupaten/kota. Tetapi praktiknyaadalah 13.818 Ha.
Grafik 3. Daftar Kegiatan Reboisasi dan Penghijauandengan Dana DAK - DR Tahun 2003
Sumber : Rencana Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2003
Berdasarkan master plan Dinas Kehutanan Propinsi Riau tersebutdi atas pada tahun 2003, kawasan yang dicadangkan untuk rehabilitasi
REDD: Antitesis Reboisasi?
61Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
hutan adalah seluas 16.765 ha dan penghijauan seluas 5.141 hadengan total kawasan yang akan direhabilitasi seluas 21.906 ha.Berdasarkan hasil kegiatan dari pelaksanaan rencana, hanyadilakukan di kawasan seluas 2.090 ha, dapat diperkirakan hanyaterlaksana sekitar 10 %. Sedangkan pada tahun 2004, rehabilitasihutan direncanakan pada kawasan seluas 16.105 ha di enamkabupaten/kota, dan dalam pelaksanaannya berkisar 13.818 ha.Adapun untuk Izin Hutan Tanaman Industri seluas 51.716 hadikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Dari gambarantersebut diatas jika dibandingkan antara kebijakan rehabilitasi yangada dengan izin yang dikeluarkan untuk HTI, berbeda jauh luasanyang diberikan untuk izin HTI dibanding dengan kebijakan luasanuntuk rehabilitasi terhadap hutan. Apabila dilihat dalam praktekpelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan, ternyata tidak dilaksanakansecara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa dalam politik hukumterhadap kebijakan kehutanan hingga saat ini belum terjadi sebuahperubahan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hutan yangada di Riau.
3. Suaka Margasatwa (SM) Rimbang BalingSuaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling ditetapkan sebagai
kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982. Landscape zona intikawasan SM Rimbang Baling berdasarkan keputusan tersebut adalahseluas 136 ribu ha. SM Rimbang Baling berada di wilayahadministratif dua propinsi, yakni Propinsi Riau dan Sumatera Barat.Di Propinsi Riau, landscape SM Rimbang Baling berada di KabupatenKampar dan Kuantan Singingi; sedangkan yang di Propinsi SumateraBarat terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi SM BukitRimbang Baling berada di hulu Sungai Kampar, tepatnya pada posisi0° 08' - 0° 37' Lintang Selatan dan 100° 48' - 101° 17' Bujur Timur;dengan jarak 115 km dari Kota Pekanbaru, Ibu Kota Propinsi Riau.
REDD: Antitesis Reboisasi?
62 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 4. Profil Suaka Margasatwa (SM)Bukit Rimbang Bukit Baling
Nama Area Suaka Margasatwa (SM) BukitRimbang Bukit Baling
Status Suaka MargasatwaLuas (Ha) 136.000 HektarSurat Keputusan SK Gubernur KDH TK. I No
149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982Letak Administratif Area Kabupaten Kampar dan
Kabupaten Kuantan SingingiPotensi Flora Meranti (Shorea.SP),Kempas
(Koompassia malacensisMaig),Balam (PalaqiumGulta),Durian Hutan (Durio SP),Rotan (Calamus cirearus),Terentang (Campnosperma spp), dll
Potensi Fauna Harimau Dahan(Neofelisnebulosa), HarimauLoreng Sumatra (Panthera tigrissumatrensis), Tapir (Tapirusindicus), Siamang(Syimphalangus syndactitylus),Kukang(Nycticebus caucang),Rusa (Cervus timorensi), Kancil(Tragulus javanicus), Lutung(Presbytis cristata), BeruangMadu (Helarctosmalayanus), dll.
Tantangan Kawasan 1. Pemukiman dalam kawasansepanjang sungai Sebayangyang terletak di tengah-tengah kawasan (pemu-kiman sudah ada sebelumSK penunjukan kawasan)
2. Perambahan dan pencu-rian kayu, dll.
Sumber : Diolah dari Arsip Scale Up, 2009
REDD: Antitesis Reboisasi?
63Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Nama Rimbang Baling diambil dari nama dua bukit di kawasantersebut, yakni Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Berbeda misalnyadengan SM Kerumutan atau atau SM Danau Tasik Besar diSemenanjung Kampar yang merupakan hutan dataran rendah, SMRimbang Baling merupakan satu-satunya kawasan lindung di Riauyang bernuansa perbukitan. Di sinilah hulu Sungai Kampar.
Topografi kawasan ini bergelombang, berbukit, dan merupakanekosistem hutan hujan dataran rendah, dengan kemiringan 25-100%dan ketinggian 927-1070 meter di atas permukaan laut. TopografiSM Rimbang Baling tidak berbeda dengan Sumatera Barat. Ini dapatdimengerti karena landscape kawasan ini memang berada di sekitarBukit Barisan. Iklim di kawasan SM Rimbang Baling termasuk dalamklasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, yang termasuk dalam tipeA dengan Q antara 0-14%.
Landscape SM Rimbang Baling berada di hulu Sungai Kampar(melalui Sungai Sebayang), dan Sungai Indragiri (melalui Sungai
REDD: Antitesis Reboisasi?
64 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Suaka Margasatwa Rimbang Baling, kawasan lindung berbukit yang dialirioleh hulu Sungai Kampar, kaya akan potensi hutan alam yang besar dan patutdijaga kelestariannya. sumber : scale up
Singingi). Beberapa sub daerah aliran sungai di kawasan SM RimbangBaling antara lain Sungai Sebayang (anak Sungai Kampar), danSungai Singingi (anak Sungai Indragiri). Keberadaan PLTA KotoPanjang, juga bergantung pada kemurahan hati kawasan ini mengaliriair. Karena itu, keberadaan hutan di kawasan ini menjadi sangatberpengaruh terhadap kawasan di hilir.
4. Land Use dan Ancaman Ekosistem SMRimbang Baling
Pemaparan terhadap ancaman terhadap SM Rimbang Baling akanbertolak dari pengelompokan kawasan ke dalam dua kategori,pertama ancaman di zona inti, kedua ancaman di zona penyanggaSM Rimbang Baling. Berdasarkan intensitas dan tingkatketerancamannya, ada beberapa kegiatan yang mengancamkeberadaan suaka margasatwa dan ekosistem Rimbang Baling,seperti aktivitas illegal logging, perambahan yang dilakukan oleh wargauntuk pertanian dan perkebunan, perluasan pemukiman kampung,perburuan satwa liar, serta pembukaan akses jalan antara kampungyang berada di zona inti SM Rimbang Baling.
1. Illegal loggingTidak berbeda dengan tempat lain di Riau, kawasan SM Rimbang
Baling pernah menjadi taman surgawi para pelaku illegal logging. DiDesa Kuntu misalnya, pada masa penegakan hukum terhadap parapelaku illegal logging belum ketat seperti pada masa pemerintahanSusilo Bambang Yudoyono (SBY), sebagian besar warga adalah parapelaku penebangan tanpa izin (Wawancara Jafri, 3/3/2010). Kiniaktivitas penebangan liar sudah agak berkurang terutama sejakperiode pertama pemerintahan SBY. Mayoritas mantan aktivis illegallogging sudah mulai mengalihkan sumber mata pencaharian merekake aktivitas perkebunan, terutama perkebunan sawit, dan atausebagian lainnya kembali menekuni perkebunan karet.
REDD: Antitesis Reboisasi?
65Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Meski demikian, tidak berarti aktivitas penebangan kayu log tanpaizin berhenti sama sekali. Saat melakukan pengumpulan datalapangan, peneliti menemukan beberapa orang warga yang sedangmelakukan pengangkutan kayu hasil penebangan liar di kawasanSM Rimbang Baling. Kayu dari hulu dihanyutkan melalui SungaiSebayang sampai ke pelabuhan di Pasar Gema, Kecamatan KamparKiri Hulu. Kayu log berdiameter sekitar 50 centimeter dan panjangrata-rata enam meter ini, menurut informasi warga yang kamiwawancari diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sawmills disekitar Kampar Kiri Hulu. Sedikitnya dua minggu sekali puluhantual kayu log yang dihanyutkan dari hulu Sungai Sebayang (zonainti SM Rimbang Baling) sampai ke pelabuhan di Pasar Gema(Wawancara warga, 3/3/2010). Keberadaan Sungai Sebayangmemang sangat membantu mempermudah aktivitas pengangkutankayu log dari hulu Sungai Sebayang.
REDD: Antitesis Reboisasi?
66 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat karena tekananekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permintaan hasilpenebangan liar ini sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk dihentikan.sumber : scale up
2. Perambahan untuk Areal Pertanian dan PerkebunanPerambahan hutan di kawasan SM Rimbang Baling yang
dilakukan oleh warga tempatan adalah terkait dengan aktivitaspeladangan dan pembangunan perkebunan karet. Sedikitnya adaenam kampung yang berada di zona inti SM Rimbang Baling.Mayoritas penduduk mengandalkan pertanian terutama peladangandan perkebunan karet sebagai sumber mata pencaharian utama.Aktivitas peladangan warga masih menggunakan sistem tadah hujandengan lokasi peladangan yang berpindah-pindah.
Sistem peladangan berpindah-pindah yang dilakukan warga dikawasan zona inti SM Rimbang Baling dalam pemantauansebenarnya bukan ancaman yang sangat serius terhadap keberadaanhutan di kawasan ini, sedikitnya karena tiga alasan. Pertama, karenapopulasi penduduk di kawasan zona inti belum begitu banyakdibandingkan dengan luasan zona inti Rimbang Baling. Kedua, bekaspeladangan warga yang ditinggalkan biasanya dalam waktu yangtidak lama (5-10 tahun) segera kembali menjadi hutan. Sebagianmasyarakat memang menanami karet di areal bekas peladangan,tapi sebagian besar lainnya membiarkan areal bekas peladanganmereka, sehingga kawasan tersebut segera menjadi hutan. Ketiga,kearifan lokal dan sistem nilai tradisional masyarakat dalampengaturan teknologi ruang memungkinkan terjaganya sustainibilitassumber daya hutan di kawasan tersebut.
3. Pemekaran desa dan perluasan pemukiman kampungSedikitnya terdapat delapan kampung yang berada di zona inti
SM Rimbang Baling, yakni desa Batu Sanggan, Aur Kuning, MuaraBio, Gajah Betaluik, Terusan, Subayang Jaya, Tanjung Beringin, danPangkalan Serai. Dua desa yang disebutkan pertama yakni BatuSanggan dan Aur Kuning merupakan perkampungan lama yangsudah didiami sejak ratusan tahun lalu, sementara enam desa lainnyamerupakan desa pemekaran dari desa Batu Sanggan dan Aur Kuning
REDD: Antitesis Reboisasi?
67Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pada tahun 2003. Delapan desa ini berada di wilayah administratifKecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
Memang disadari bahwa keberadaan aktivitas perekonomianwarga yang berbasis lahan di zona inti SM Rimbang Balingmerupakan permasalahan cukup serius terkait pengaturan keruangankawasan ini. Di satu pihak kawasan ini sudah ditetapkan sebagaikawasan lindung semenjak hampir tiga dekade lalu, namun di pihaklain, pemerintah daerah (Kabupaten Kampar) melakukanpembentukan satuan administratif pemerintahan baru setingkat desadi kawasan ini. Di satu pihak pembentukan desa merupakankebutuhan untuk mempermudah layanan pembangunan bagimasyarakat yang memang telah mendiami kawasan ini sejak lama;namun di pihak lain, hal ini akan menjadi bom waktu bagi masadepan kawasan lindung ini.
Keberadaan perkampungan di zona inti dan pertumbuhanpopulasi yang dipastikan akan semakin meningkat, menjadikanperluasan areal pemukiman sebagai sesuatu kebutuhan yang tidakterelakkan. Karena itu, penyelesaian masalah status desa di zonainti Rimbang Baling merupakan masalah yang mendesakdiselesaikan pemerintah. Masyarakat desa di zona inti SM RimbangBaling sendiri sudah lama mendesak pemerintah agarperkampungan mereka dikeluarkan dari areal kawasan lindung.Mereka bahkan merasa dikelabui pemerintah saat mengetahuiwilayah desa mereka pada 1982 lalu tiba-tiba ditetapkan sebagaikawasan lindung.
Terkait upaya pemecahan masalah tersebut, Raflis, aktivis KabutRiau mengatakan bahwa berdasarkan UU No 26/2007 tentangRTRW Kawasan Lindung, keberadaan masyarakat di kawasanlindung mungkin saja terjadi dan pemerintah dapat menerapkanreward and punishment sebagai kompensasi pemakaian kawasanlindung. Ini berarti masyarakat dapat tetap tinggal dan beraktivitas,namun harus berkomitmen dan bertanggung jawab menjaga kawasanlindung tersebut (Media Indonesia, 7/3/2009).
REDD: Antitesis Reboisasi?
68 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
4. Perburuan satwa liarBerdasarkan informasi dari masyarakat maupun ditemukan
langsung oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data lapangan,masing sangat banyak satwa yang hidup di areal hutan ini. Bustamirdan Yusman menyebutkan bahwa beberapa satwa yang masihditemukan di kawasan Rimbang Baling antara lain harimau sumatera,badak sumatera, rusa, tapir, ular sanca, babi hutan, monyet ekorpanjang, beruk, siamang, simpai, lutuh dada putih, napu, kancil,beruang madu, burung elang, burung murai batu, ikan tomang, ikangadis, ikan lemak, ikan kumuh, dan ikan baung. Namun perburuanterhadap satwa liar masih menjadi ancaman bagi kelestarianekosistem di kawasan ini. Hal ini diakibatkan oleh beberapa halantara lain :1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
perlindungan satwa liar;2) Permintaan pasar gelap terhadap harimau sumatera, beruang,
buaya, ikan arwana, dan bagian tubuhnya sangat tinggi;3) Lemahnya penegakan hukum;4) Tingginya konflik satwa dan manusia.
Perburuan satwa liar khususnya harimau sumatera di kawasanini cukup tinggi terutama karena terkait dengan adanya pembeli,akses, dan tempat penjualan yang relatif mudah. Teridentifikasiada 12 orang pemburu dan penadah harimau sumatera, 15 orangpemburu rusa dan babi (mangsa harimau). Pemburu mangsaharimau ini terkadang juga akan menangkap harimau jika kenajerat (YASA, 2005). Maraknya pemburuan harimau ini disebabkanoleh harganya yang tinggi, hasil penjualan rata-rata harimau Rp.25 juta rupiah, dagingnya rata-rata Rp. 80.100/kg, dan bagiantubuhnya (mulai dari kumis, kuku, penis, tengkorak hinggakulitnya) harga rata-rata Rp. 115.700 hingga rata-rata dapatdihargai Rp. 18.342.900, tergantung dari jenis harimaunya (TrafficSEA, 2004).
REDD: Antitesis Reboisasi?
69Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
5. Pembukaan akses jalan di zona inti SM Rimbang BalingJefri Noer, mantan Bupati Kampar yang dilengserkan akibat people
power masyarakat Kampar pada tahun 2002 lalu, bisa benar-benarbermaksud memudahkan pelayanan masyarakat di kawasan RimbangBaling, ketika dia membuka akses jalan di zona inti kawasan lindungtersebut. Namun upayanya menuai kontroversi, banyak orang menilaiupaya tersebut seperti meretas jalan untuk mengangkut kayu darihutan lindung Rimbang Baling. Perdebatan pun menguat, sehinggapada akhirnya pembukaan jalan tersebut dibatalkan karena tidakmendapatkan izin Menteri Kehutanan. Saat peneliti menelusuriSungai Sebayang, bekas jalan rintisan era pemerintahan Jefri Noermulai ditumbuhi pohon dan mulai kembali menghutan, meskipunbelum mampu menyembunyikan bekasnya.
Gambar 2. Peta Survei Pembukaan Lahan di Rimbang Baling
Sumber Peta : http://raflis.wordpress.com/2009/05/17/
REDD: Antitesis Reboisasi?
70 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Hingga saat ini pembukaan akses jalan di zona inti RimbangBaling masih selalu menghantui kawasan ini. Pasalnya, delapanperkampungan di zona inti SM Rimbang Baling merupakan daerahterisolasi, dengan populasi yang memiliki tingkat angka kemiskinansangat tinggi akibat lokasi perkampungan yang sangat terisolasi.Pembukaan akses jalan antar kampung di kawasan tersebutmerupakan alternatif paling memungkinkan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakatnya. Sebab, selama ini satu-satunya alattransportasi menuju desa-desa di kawasan tersebut adalah denganmelewati jalur sungai. Namun masalahnya, dari perspektifkonservasi, pembukaan akses jalan selalu menjadi ancaman bagikelestarian hutan di kawasan bersangkutan.
Aktivitas perambahan dan perusakan tidak saja terjadi di dalamkawasan zona inti SM Rimbang Baling, tetapi juga terjadi di sekitarkawasan tersebut. Beberapa aktivitas di sekitar SM Rimbang Balingyang menjadi ancaman diantaranya :1) Di sisi Barat kawasan SM Rimbang Baling, tepatnya di Kecamatan
Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, ancaman nyata dariekspansi besar-besaran industri pertambangan batu bara PTManunggal Inti Arthamas (MIA) meninggalkan lubangmenganga bekas areal pertambangan. Dibandingkan denganeksploitasi sumber daya hutan, pertambangan batu barasesungguhnya menimbulkan dampak ekologis yang jauh lebihbesar, karena areal bekas pertambangan biasanya sulit untukditumbuhi pepohonan meski sudah ditinggalkan selama puluhantahun.
REDD: Antitesis Reboisasi?
71Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sumber foto : matanews.com
2) Di sekitar kawasan di sisi Barat SM Rimbang Baling ditemukanpula aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) disepanjang bantaran Sungai Singingi. Aktivitas PETI membuatsungai berdasar kerikil yang dulunya jernih menjadi keruhbercampur tanah. Aktivitas ini tentu merupakan ancaman seriusterhadap keberadaan satwa air di sepanjang sungai tersebut;
3) Makin banyaknya perkebunan sawit yang dibuka warga secarapribadi maupun oleh perusahaan. Perkebunan sawit skala besarantara lain dibuka oleh Kebun Pantai Raja. Lokasinya berada diwilayah Kuntu, Kabupaten Kampar. Pasca era illegal logging,masyarakat secara massal sudah mulai mengalihkan orientasiekonomi mereka ke perkebunan sawit. Di bagian Barat RimbangBaling, di wilayah administatif Kabupaten Kuantan Singingi,pesona perkebunan sawit pun sudah berhasil menggodamasyarakat;
REDD: Antitesis Reboisasi?
72 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Aktivitas penambangan batubara terlihat di lokasi yang berbatasan langsungdengan Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling di KecamatanSingingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. sumber : matanews.com
Seseorang yang menuju desa Batu Sanggan misalnya, sepanjangperjalanan mereka akan terasa seperti dikawal dengan perkebunansawit. Di Batu Sanggan dan Pangkalan Indarung, masyarakatdan para informan yang kami temui menceritakan keinginan kuatmereka untuk menghadirkan investor di bidang persawitan yangbersedia bekerjasama dengan mereka membangun perkebunansawit di kampung mereka. Namun, sejauh ini, beberapa investoryang sudah mendatangi lokasi di kawasan tersebut selalumembatalkan rencana setelah mengetahui status areal sebagaikawasan lindung;
4) Perusahaan yang bergerak di bidang HTI, seperti yang dilakukanPT. RAPP di wilayah Kuntu. Keberadaan HTI di sekitar kawasanSM Rimbang Baling menurut Bustamir merupakan ancaman bagieksistensi zona inti Rimbang Baling. Pasalnya, tanaman jenisakasia di HTI sifatnya ekspansif. Bibit akasia dapat berkembangdengan cepat akibat dibawa angin dan bibitnya sangat mudahtumbuh secara alamiah. Apabila keberadaan hutan tanamanindustri di sekitar kawasan Rimbang Baling tetap dibiarkan dalamkurun waktu yang lama, Bustamir memperkirakan tidak sampai
REDD: Antitesis Reboisasi?
73Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sejak permintaan sawit semakin tinggi di pasaran, keterancaman terhadap ar-eal kawasan hutan alam dan hutan lindung juga ikut tinggi. sumber : scale up
lima puluh tahun ke depan, Bukit Rimbang Baling akan berubahmenjadi hutan akasia, meskipun tidak menjadi area konsesiperusahaan HTI (Wawancara Bustamir, 4/3/2010).
Penting dikemukakan bahwa selain ancaman-ancaman yangdisebutkan di atas, juga terdapat beberapa hal yang berpotensimenjadi ancaman bagi kelestarian SM Rimbang Baling. Sebut sajamisalnya: (1) Pemberian ijin oleh pemerintah yang tidak sesuaidengan peruntukan dan kelayakan; (2) Kurangnya komitmenDepartemen Kehutanan dalam menjalankan verifikasi ijin HTI semiillegal; (3) Kebijakan Departemen Kehutanan untuk mempercepatpembangunan HTI; (4) Kebijakan pemerintah propinsi dankabupaten dalam mengembangkan perkebunan sawit; (5) Peruntukanpengembangan sawit rakyat yang tidak tepat; (6) Tidak sinkronnyapenataan ruang propinsi dan kabupaten, dan; (7) Lemahnyaperangkat perundangan dalam mengatur perkebunan small holder.Persoalan-persoalan tersebut berpotensi menjadi ancaman bagikeberadaan SM Rimbang Baling.
3.1.2. REVIEW KONDISI SOSIAL EKONOMI DANBUDAYA DI RIMBANG BALING
1. Kampung-Kampung di Rimbang BalingPerkampungan di Suaka Margasatwa dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori. Pertama, perkampungan yang berada di zonainti, dan kedua, perkampungan yang berada di zona penyangga SMRimbang Baling. Ada delapan kampung yang berada di dalam zonainti, yakni Batu Sanggan, Aur Kuning, Muara Bio, Gajah Betaluik,Terusan, Subayang Jaya, Tanjung Beringin, dan Pangkalan Serai.Dua desa yang disebutkan pertama yakni Batu Sanggan dan AurKuning merupakan perkampungan lama yang sudah didiami sejakratusan tahun lalu, sementara enam desa lainnya merupakan desa
REDD: Antitesis Reboisasi?
74 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pemekaran dari desa Batu Sanggan dan Aur Kuning, pada tahun2003. Delapan desa ini berada di wilayah administratif KecamatanKampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
Kampung-kampung yang berada di zona penyangga berada diwilayah administratif Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi.Adapun perkampungan yang berada di zona penyangga yang beradadi wilayah administratif Kabupaten Kampar adalah Desa Kuntu,Pangkalan Kapas, Kebun Tinggi, Padang Sawah, Domo, TanjungBelit Selatan, Gema, Tanjung Belit, Sungai Paku, dan Balung.Sedangkan yang berada di wilayah administratif Kabupaten KuantanSingingi adalah Desa Pangkalan Indarung, Tanjung Karang, KotoBaru, Petai, dan Desa Pulau Padang.
Meski merupakan perkampungan baru, menurut Yusman, tokohadat setempat yang bergelar Datuk Tumenggung Pucuk BatuSanggan, penghuni kampung yang berada di zona inti SM RimbangBaling sudah ratusan tahun mendiami kawasan itu. Narasi lokaldaerah setempat secara meyakinkan menunjukkan keberadaanperkampungan ini sudah existing pada ratusan tahun lalu. Pemberiannama kampung dengan nama-nama berdasarkan peristiwa tertentumenandakan kefasihan ingatan warga setempat terhadap peristiwa-peristiwa historis di daerah tersebut yang kemudian diabadikan dalambentuk penamaan kampung bersangkutan.
Tersebutlah kisah bahwa asal usul nama Batu Sanggan misalnya,diyakini terkait peristiwa perburuan Gagak Jaoh mencari PutriLindung Bulan. Naskah Sejarah Adat dan Istiadat Kampar Kiri karyaHaji Ibrahim dan Khalifah Muhammad Isa menyebutkan bahwaBatu Sanggan merupakan lokasi terakhir perjalanan Gagak Jaoh,seorang Hulu Balang Raja Portugal, mencari Putri Lindung Bulan(Ibrahim,1939:33-35). Putri Lindung Bulan merupakan seorang putricantik bermukim di Sungai Batang Siantan, sebuah negeri yang kinisudah tidak ada lagi. Suatu waktu yang tidak disebutkan tahunnya,seorang Hulu Balang Portugal bernama Gagak Jaoh datang ke negeriitu dengan maksud hendak menaklukkan Rantau Kampar Kiri dan
REDD: Antitesis Reboisasi?
75Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
menculik Putri Lindung Bulan.Mendengar kabar kedatangan pasukan Portugal, penduduk negeri
Batang Siantan bersama Putri Lindung Bulan melarikan dirimenelusuri Sungai Sebayang. Gagak Jaoh mengikuti pelarian putribeserta penduduk negeri itu. Sampai ke sebuah lokasi di hulutersebut, Gagak Jaoh berhenti karena setelah jauh berjalan tetaptidak menemukan putri yang dicari. Di lokasi tersebut, dia beristirahatdan mengasah pedangnya. Untuk memastikan pedang yang diasahsudah tajam, dia memukulkan pedangnya ke sebuah batu hinggaterbelah menjadi dua bagian. Lokasi tersebut kemudian dinamakanBatu Sanggan. Nama “Batu Sanggan” menurut Bustamir, KhalifahKuntu maksudnya “sehingga di situlah Gagak Jaoh berjalan”(Wawancara Bustamir, 7/3/2010). Batu tersebut menurut informasiwarga hingga sekarang masih bisa ditemukan beberapa meter darilokasi pemukiman warga Batu Sanggan.
Nama Kuntu, sebuah desa yang berada di zona penyanggakawasan Rimbang Baling juga diambil dari peristiwa yang terkaitdengan kedatangan Gagak Jaoh. Pada bagian lain cerita tersebutdikisahkan bahwa saat sedang melarikan diri, Putri Lindung Bulansempat terjatuh dan secara reflek mengucapkan kata “KuntuTuroban”. Lokasi jatuhnya putri ini belakangan diabadikan sebagainama kampung yang dibangun setelah rombongan sang putri pulangdari pelarian akibat serangan Hulu Balang Gagak Jaoh (Ibra-him,1939:33-35). Meski teori bahwa Kuntu berasal dari ucapan PutriLindung Bulan dibantah Bustamir, karena menurutnya nama tersebutdiberikan oleh seorang Ulama asal Timur Tengah utusan DinastiFatimiyah yang datang ke daerah ini, dan tidak terkait dengan ucapanPutri Lindung Bulan. Bustamir sependapat dengan Ibrahim bahwakata “kuntu” sendiri memang berasal dari bahasa Arab (WawancaraBustamir, 7/3/2010).
Yusman, Datuk Tumenggung Pucuk Batu Sanggan menceritakanbahwa pada masa Kerajaan Pagaruyung, Batu Sanggan berada dalamwilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Sumatera Barat ini.
REDD: Antitesis Reboisasi?
76 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Pada masa peperangan Padri, Batu Sanggan dipimpin dalam satukekhalifahan (wali nagari) yang berada di Lipat Kain, salah satunegeri yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Gunung Sahilan.Kerajaan Gunung Sahilan dilaporkan sudah tidak ada lagi saatkemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Beberapa tokohmasyarakat yang kami temui di Batu Sanggan masih mengingat saat-saat kawasan perkampungan mereka menjadi salah satu pusatperlawanan pasukan PRRI (Pemberontakan Revolusioner RepublikIndonesia) menghadapi pasukan Republik Indonesia.
Penggalan kisah di atas menandakan bahwa beberapa pemukimanyang berada di zona inti Rimbang Baling sudah dihuni warga jauhsebelum pemerintah pusat menetapkan kawasan ini pada tahun 1982sebagai kawasan lindung suaka margasatwa. Karena itu Yusmanmengaku sangat terkejut ketika membaca studi kelayakan sebagai dasarpenetapan kawasan itu menjadi suaka margasatwa. Dalam studidimaksud disebutkan bahwa di Batu Sanggan dilaporkan hanya terdapatempat buah rumah. Padahal menurutnya, sebelum tahun 1982, di lokasitersebut sudah menjadi perkampungan. Menurut Yusman, pada saatitu pemerintah dengan sengaja memanipulasi data dengan menyatakandaerah Rimbang Baling sebagai daerah tidak berpenghuni dan bisaditetapkan sebagai kawasan lindung (Wawancara 7/3/2010).
Saat melakukan pengambilan data lapangan di lapangan, kamiberkeyakinan bahwa perkampungan yang berada di sepanjang SungaiSebayang di kawasan Rimbang Baling masih berdiri rumah-rumahlama yang berusia lebih dari setengah abad. Di Batu Sanggan masihditemukan belasan rumah yang masih berdiri kokoh meskiberdasarkan informasi warga rumah tersebut sudah dibangun saatperang kemerdekaan ataupun pada masa pemberontakan PRRI.Yusman meyakinkan bahwa pada akhir tahun 1960-an memangpernah terjadi banjir besar yang menghanyutkan sebagian besarrumah di Batu Sanggan dan rumah-rumah di perkampungan lainnyayang ada sepanjang Sungai Sebayang; namun setelah banjir selesaiwarga kembali membangun rumah mereka di lokasi yang sama.
REDD: Antitesis Reboisasi?
77Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Kenyataan adanya perkampungan di kawasan Suaka MargasatwaRimbang Baling ini sesungguhnya merupakan permasalahan utamayang melingkupi masyarakat desa di kawasan ini. Mereka mengakukebingungan dengan sikap pemerintah, yang di satu pihak tidakmengakui keberadaan desa mereka, tapi di pihak lain pemerintahmenerbitkan kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan adanyapengakuan keabsahan keberadaan desa-desa di kawasan ini.Pemekaran desa Batu Sanggan dan Aur Kuning menjadi delapandesa misalnya, merupakan petunjuk ada pengakuan negara ataskeberadaan perkampungan di zona lindung ini. Namun di pihaklain masyarakat di kawasan tersebut tidak dibenarkan memilikikepemilikan tanah secara pribadi. Masyarakat desa Batu Sangganmisalnya tidak seorang pun yang memiliki surat kepemilikan tanah,tetapi cukup mengherankan bahwa negara mewajibkan pembayaranpajak bumi dan bangunan.
Di Pangkalan Indarung, salah satu desa yang secara administratifberada di zona penyangga, mengeluhkan status desa mereka sebagai
REDD: Antitesis Reboisasi?
78 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Perkampungan masyarakat di Rimbang Baling sangat akrab denganlingkungan di sekitar aliran sungai karena aliran ini memberikan sumberpenghidupan. Pengakuan oleh pemerintah terhadap keabsahan wilayah di desasekitar saat ini masih menjadi polemik. sumber : scale up
bagian dari kawasan lindung. Seorang anggota Badan PerwakilanDesa di Pangkalan Indarung yang diwawancarai mengatakan bahwastatus desa sebagai bagian dari kawasan lindung menjadikan desamereka selalu menghadapi kendala apabila ada investor yang inginmenanamkan modal perkebunan sawit di wilayah desa mereka. DiBatu Sanggan masyarakat membentuk kelompok koperasi denganmaksud agar bisa menarik investor yang hendak menanamkan modaldi desa mereka. Tetapi juga terkendala karena status kawasan yangmerupakan kawasan lindung.
2. Kondisi Sosial Budaya dan EkonomiKarakteristik keragaman etnis dan latar belakang sejarah
penduduk yang mendiami daerah Rimbang Baling memberi corakyang khas terhadap struktur sosial dan kehidupan sosial budaya diberbagai kampung lokasi studi. Mayoritas penduduk di desa-desayang berada di kawasan SM Rimbang Baling merupakan masyarakatetnis melayu, namun demikian ditemui juga etnis lainnya pada setiapdesa di kawasan tersebut seperti misalnya etnis Minang dan Jawa,meski sangat sedikit jumlahnya.
Meski etnis Melayu mayoritas, namun demikian dalam kehidupanmasyarakat yang heterogen di daerah ini hingga kini mereka dapathidup berdampingan secara rukun, damai dan saling menghargaiperbedaan. Keadaan masyarakat Melayu yang terbuka dan etnispendatang umumnya juga cepat beradaptasi dengan adat dan budayaetnis tempatan, membuat kehidupan masyarakat di zona intiRimbang Baling ini relatif harmonis.
Struktur hubungan sosial berdasarkan ikatan tradisional danprimordial masih cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat desa.Peran ketokohan dan kepemimpinan biasanya berada pada orang-orang atau keturunan keluarga yang lebih awal mendiami daerahini. Di samping itu, sistem pelapisan sosial ekonomi juga tak kalahpentingnya memberi corak bagi struktur sosial dalam masyarakatperdesaan di kawasan Rimbang Baling. Hal ini tentu sangat terkait
REDD: Antitesis Reboisasi?
79Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dengan riwayat pemukiman yang berlangsung di berbagai penjurudi kawasan ini yang juga tidak terlepas dari pengaruh penetrasi nilaiekonomi. Berdasarkan struktur sosial seperti ini maka di masing-masing desa biasanya dapat ditemui adanya individu-individu yangdiklasifikasikan sebagai tokoh masyarakat. Selain adanya tokohmasyarakat dari etnis Melayu yang digolongkan sebagai kelompoketnis tempatan, mayoritas dan dominan, pada setiap etnis pendatangbiasanya juga ditemukan adanya representasi tokoh etnisnya yangjuga digolongkan sebagai tokoh masyarakat desa.
Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari perkampungan dikawasan ini juga terlihat gambaran otoritas ganda melaluikepemimpinan Kepala Desa di satu pihak dan Kepemimpinan Adatdi pihak lain. Keduanya memiliki kedudukan sentral dan penting.Kepemimpinan kepala desa terutama dalam urusan resmi danadministrasi pemerintahan, dan tentu saja meliputi urusan-urusansosial kemasyarakatan. Sedangkan kepemimpinan adat lebih banyakmenangani urusan sosial budaya atau adat istiadat di kampung. Figurkepala desa memiliki pengaruh melampaui otoritas kepemimpinanadat manakala didukung oleh kharisma kepribadiannya yang jujur,berwibawa, dan bijaksana. Pengaruhnya biasanya menjadi semakinbesar lagi apabila ia berasal dari lapisan kaya dan keturunan pendirikampung. Sementara kepemimpinan adat memiliki otoritas yangstabil dan kuat meskipun untuk sebagian besar mereka tidakdidukung oleh faktor-faktor ekonomi.
Dalam sistem kepemilikan lahan, umumnya masyarakat dikawasan zona inti Rimbang Baling ini mengenal adanya lahan milikindividu/keluarga dan lahan ulayat desa. Setiap individu/keluargadi Batu Sanggan misalnya, dapat dikatakan umumnya memiliki lahanterutama untuk kebun atau ladang yang digunakan sebagai lahanpertanian, meski dalam soal lahan pekarangan perumahan tidakdikenal kepemilikan personal. Tidak ada transaksi jual beli untuklahan perumahan, sebab di dalam pola kepemilikan lahanperumahan, kepemilikannya dalam bentuk komunal atau persukuan.
REDD: Antitesis Reboisasi?
80 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Warga yang ingin membangun rumah cukup meminta izin kepadapimpinan persukuan, lalu pimpinan persukuan yang mencarikanlahan untuk pembangunan rumah. Tidak ada surat resmi tentangkepemilikan lahan di kawasan ini mengingat lokasi tersebut beradadi kawasan hutan lindung.
Berbeda halnya dengan perkampungan yang berada di zonapenyangga SM Rimbang Baling. Di desa-desa ini ditemukankepemilikan tanah secara pribadi berikut surat bukti kepemilikantanah seperti umumnya di tempat lain di Indonesia. Diperkampungan yang merupakan zona penyangga juga ditemukantanah yang merupakan area konsesi perusahaan yang biasanya secaralangsung pengurusannya dilakukan lewat otoritas pemerintahansupra desa, pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Tidak adanya otoritas desa terkait penguasaan tanah oleh perusahaaninilah antara lain yang menimbulkan konflik antara masyarakatdengan perusahaan disebabkan adanya klaim hak atas lahan konsesiperusahaan oleh masyarakat desa.
REDD: Antitesis Reboisasi?
81Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Kehidupan masyarakat di kawasan zona inti Rimbang Baling, mengenal sistemkepemilikan lahan yang dikuasai oleh individu/keluarga dan lahan ulayat desa.sumber : scale up
Lahan yang belum diolah atau belum ditanami oleh masyarakatbiasanya dipandang sebagai ulayat desa. Lahan yang semula telahdiolah oleh individu ketika tidak dimanfaatkan lagi dalam kurunwaktu yang lama, maka hak atas lahan tersebut akan kembali menjadiulayat desa dan otoritasnya ada pada pemerintahan desa ataupunotoritas adat. Tanah dan lahan yang sudah dikelola oleh individu/keluarga di zona inti Rimbang Baling dapat diwariskan kepada anak-anak berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga bersangkutan meskitanpa diikuti dengan surat resmi dari negara. Dengan adanya sistemkepemilikan individual seperti ini maka pengalihan hak atas tanahkepada pihak lain relatif lebih longgar.
Kehidupan masyarakat desa umumnya juga masih ditandai coraktradisional dan agamis. Nilai tradisional dominan bersumber darikebudayaan kelompok dominan etnis Melayu. Dalam kehidupansosial masyarakat perdesaan di daerah ini, pengaruh agama Islamjuga menonjol sebagai agama mayoritas yang juga diidentikkandengan ke-Melayu-an. Di Kuntu, desa yang berada di zonapenyangga Rimbang Baling, corak keislaman terlihat sangat kuat.Bahkan, istilah pimpinan adat di desa ini menggunakan kata KhalifahKuntu: sebuah pertanda bahwa penamaan bagi otoritas adat di desaini memiliki pertalian yang kuat dengan sistem pemerintahan yangbiasa dikenal dalam agama Islam. Ini dapat dipahami mengingatKuntu pernah menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan ini, danRiau umumnya. Di desa ini terdapat makam Syeikh Burhanuddin,seorang ulama besar berasal dari Arab yang diyakini sebagai penyebaragama Islam yang sangat berpengaruh di Riau.
Demikian halnya di Batu Sanggan, pengaruh corak keislamanterlihat sangat menguat. Mungkin ini tidak dapat dipisahkan daripengaruh PRRI, gerakan berbasis Islam yang pernah menjadikankawasan ini sebagai pusat aktivitas perlawanan mereka terhadaprepublik. Namun berbeda dengan di Kuntu dan Batu Sanggan, sayamenyaksikan kompetisi antara pengaruh agama Islam dan sistemadat sehingga memperlihatkan variansi keislaman yang khas di
REDD: Antitesis Reboisasi?
82 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
tempat tersebut. Di Pangkalan Indarung, daerah berbasis Islam dizona penyangga Rimbang Baling, saya menyaksikan pengaruh aturanadat yang relatif lebih berpengaruh dibandingkan aturan-aturanIslam; setidaknya untuk hal-hal tertentu. Ini misalnya dari fenomenakehamilan di luar nikah—suatu hal yang dilarang dalam agamaIslam—kerap kali dan biasa terjadi di desa tersebut. Meski demikianaturan adat tentang larangan mandi di sungai dengan menggunakancelana dalam sangat ditaati oleh para lelaki di desa tersebut. Dengankata lain, di satu pihak aturan agama tentang larangan perzinahantidak ditaati secara ketat, sementara aturan adat tentang laranganmandi hanya memakai celana dalam saja di sungai sangat ditaatisemua elemen masyarakat.
Meski telah mulai agak jarang dilakukan, namun beberapa bentukupacara tradisional di beberapa desa masih dapat ditemukan,terutama upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kegiatanpertanian. Salah satu tradisi upacara yang masih dilakukan ialah
REDD: Antitesis Reboisasi?
83Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sebagai salah satu sumber penghidupan, sungai bagi masyarakat di PangkalanIndarung juga sebagai tempat membersihkan diri/mandi. Aturan adat yangmelarang mandi di sungai dengan menggunakan celana dalam sangat ditaatipara kaum lelaki. sumber : scale up
upacara Semah Kampung yang biasanya dilaksanakan pada saat akanmembuka hutan atau lahan baru untuk dijadikan areal peladangan.Acara persemahan dilakukan di lokasi lahan yang akan dibuka, danbiasanya dalam upacara ini dilakukan pemotongan kambing, berdoadan makan bersama. Darah dari kambing yang disembelihditebarkan di sekitar lahan hutan yang akan dibuka. Kegiatan upacarasemah ini dipimpin oleh seseorang tokoh spritual di desa yangsekaligus memimpin doa bersama memohon kepada Yang MahaKuasa agar ladang yang akan dibuka tidak mengalami gangguanbaik dari yang bersifat nyata maupun gaib.
Di Batu Sanggan, setelah panen selesai secara rutin dilakukanacara bayar zakat. Meski hasil panen tergolong pas-pasan untukpemenuhan kebutuhan petani bersangkutan, warga di desa ini sangattaat dalam menunaikan zakat hasil pertanian apabila hasil panentelah mencapai nisab: suatu batas dimana pemilik harta tersebutwajib mengeluarkan zakat. Upacara bayar zakat selain karena alasanagama juga diyakini oleh kepercayaan tradisional bahwa harta yangtidak dizakati akan mengakibatkan bencana bagi pemiliknya.
3. Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya AlamAlam pikiran orang Melayu sesungguhnya memiliki sentuhan
yang mendalam dengan alam lingkungan sekitar. Hal inilah yangmendasari realitas bahwa orang Melayu merupakan bagian tidakterpisahkan dari lingkungan itu sendiri. Wawasan holistik itumembuat orang Melayu tidak memilahkan manusia dengan alamsekitarnya, malah keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yangsaling mendukung untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Alampikiran yang semacam itu, dalam kehidupan sehari-hari terim-plementasi dalam praktik tradisi dan upacara adat, termasuk puladalam perilaku terkait pengelolaan sumber daya alam.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifantradisional, orang Melayu di Rimbang Baling memiliki cara-caratertentu dalam memperlakukan hutan. Saat melakukan aktivitas
REDD: Antitesis Reboisasi?
84 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
peladangan, orang Melayu di Rimbang Baling tidak sesuka hatimereka mengeksploitasi hutan; melainkan terdapat sejumlah aturanyang harus dipatuhi, hal ini dimaksudkan agar kelestarian hutanyang merupakan bagian dari kehidupan mereka tetap terjaga.
A. Siklus Pertanian dan Peladangan1) Di Batu Sanggan dan di desa-desa lainnya di kawasan zona
inti Rimbang Baling, aktivitas peladangan masyarakatdilakukan secara berpindah-pindah. Areal bekas peladanganyang sudah ditanami selama beberapa tahun (biasanya limatahun atau sekitar empat kali musim tanam) ditinggalkan danmencari lokasi peladangan yang baru. Bekas peladanganbiasanya sebagian ditanami pohon karet, sedang sebagianlainnya dibiarkan tumbuh menjadi hutan kembali denganmaksud suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Inimenurut narasumber yang kami wawancarai merupakan caramasyarakat di desa-desa tersebut menghargai alam denganmemberi kesempatan agar kawasan yang sudah ditebangmenjadi ladang dapat kembali menjadi hutan. Ini menandakankearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber dayahutan;
2) Bagi orang Melayu di Rimbang Baling, yang menjadi prioritasutama dari aktivitas peladangan bukan sekedar produktivitas,tetapi adanya keanekaragaman tanaman. Hal ini dapatdipahami karena orang Melayu di Rimbang Baling bersifatsubsisten. Keanekaragaman ini diperlakukan dalam semuajenis usaha pertanian termasuk juga dalam usaha pohon karet.Dalam kegiatan berladang, yang ditanam tidak hanya tanamanpadi, tetapi ditanam pula berbagai jenis tanaman yangumurnya relatif pendek dibandingkan dengan umur padi.Tanaman tersebut antara lain seperti sayur mayur, pisang atautanaman berumur pendek lainnya yang dapat dimanfaatkanhasilnya selama mereka melakukan aktivitas peladangan di
REDD: Antitesis Reboisasi?
85Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
areal tersebut;3) Di samping menanam berbagai jenis sayur mayur di tengah
ladang, orang Melayu di Rimbang Baling jugamenyempatkan diri untuk menanam berbagai jenis pohonbuah-buahan di sekitar Banjar, seperti misalnya pohondurian, nangka, rambai, pinang, dan lain-lain. Selaindimanfaatkan hasilnya, pohon-pohon itu juga merupakanpertanda bahwa hutan tersebut sudah pernah diolah, danjika orang lain ingin membuka ladang di tempat itu, mintaizin kepada yang pertama kali membuka lahan tersebut. Iniartinya, secara tradisional, memperlihatkan adanyapengakuan bahwa penguasaan terhadap areal atau kawasantersebut berada di bawah otoritas orang yang paling pertamakali membuka areal tersebut.
Box 1. Prosesi Aktivitas Peladangan
Upacara yang biasa dilakukan terkait aktivitas peladangan.Sebelum Menotu, akan diumumkan pada hari sekian kapanharus turun ke ladang. Di situ telah dipertimbangkanperkiraan cuaca, menyesuaikan musim agar ketika beladangtidak dihadapkan pada kendala musim. Yang menentukanpara tokoh adat dan tokoh masyarakat. Ketika hendakmembuka ladang baru, seorang pawang membakarkemenyan, membikin upacara sesajian untuk minta petunjukapakah lokasi yang akan dipilih sebagai tempat membukaladang bermasalah atau tidak. Setelah mendapat petunjuk,baru dia dapat merekomendasikan. Menotu adalah aktivitasmenengok lokasi yang akan digunakan sebagai tempatpeladangan untuk memperkirakan berapa luasan lokasitersebut. Anggota kelompok di sebuah lokasi peladanganyang dibuka biasanya sekitar 15 orang, dengan diketuai
REDD: Antitesis Reboisasi?
86 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
seseorang yang disebut Tua Banjar. Merintis lokasi lahanmasing-masing. Merintis adalah menentukan sempadan.Memberi tanda-tanda ke lokasi, pembagian untuk masing-masing orang dalam anggota kelompok tersebut. Di tempatini semua seni budaya terkait aktivitas pertaniandipraktikkan. Setelah selesai merintis misalnya dilakukanupacara adat, namanya Menyoyom Banjei (semah ladang).Aktivitas yang dilakukan adalah berdoa, mohon kepadaTuhan, agar pembukaan lahan dikabulkan, tidak adahalangan saat melakukan aktivitas peladangan. Doa dipimpinoleh ulama kampung atau orang yang dinilai paling alim dikampung bersangkutan. Ritualnya membaca yasin dan tahlil.Biasanya yang menghadiri acara tersebut adalah semuaanggota banjar. Yang diundang antara lain pawang, orangpandai, tokoh, dan ulama. Perempuan membawa anak-anakmereka. Setelah disemah baru melakukan imas tombang (tobehtobang). Imas tombang adalah aktivitas membersihkan lahandengan ditebang, setelah di tebang lalu dibakar. Lalu setiaplahan dibuat jalan, berajuk, Jalan togak, jalan lintang, saatmeninjau dan menunai tadi. Ada pepatang ladang berajuk,sawah berpematang. Dibuat pelurusan sempadan. Pancangitu yang namanya rajuk (patok).Setelah ditentukan sempadanmasing-masing, kemudian menugal. Dilakukan rapat untukpenjadwalan waktu menugal (aktivitas menanam bibit).Rentang waktu 15 hari supaya tak ada selisih perbedaanumur padi di lokasi tersebut. Ini berkait dengan upaya untukmengantisipasi serangan hama padi. Kalau selisih menugalantara seseorang dengan lainnya lama, maka padi yang palingdahulu ditanam dan yang paling terakhir ditanam sangatpotensial untuk diserang hama padi. Musyawarah banjar,sering dilakukan di banjar untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul terkait aktivitas peladangan. Bahkan
REDD: Antitesis Reboisasi?
87Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
rumah banjar kadang dibuat secara digotong-royong. Rumahbanjar berfungsi sebagai tempat pertemuan untukmenyelesaikan masalah-masalah peladangan. Kalau adahama, dulu tidak ada pestisida, maka pawang membuattangkal untuk mengatasi hama. Tangkal proses pembuatanbahannya adalah dari daun, dibuat dari daun dan ditulisrajah arab. Berikutnya adalah musim basiang, yaitu aktivitasmembersihkan tanaman dari semak-semak atau rerumputan.Dilakukan bersamaan. Proses berikutnya mengawal darihama. Setelah lewat tiga bulan tibalah musim panen. Panendisebut menuai. Menuai dilakukan dengan tuai, bukandengan sabit. Dilakukan laki-laki dan perempuan. Setelahdituai, dijemur sedikit untuk memastikan padi kering. Baruditumpuk di tempat penyimpanan padi (kopuak). Sumber:Wawancara Bustamir dan Yusman, 7-12 Maret 2010
B. Lubuk Larangan di Rimbang BalingTerkait dengan pengelolaan sumber daya air dan ikan di daerah
aliran sungai di sekitar kawasan Rimbang Baling masyarakat setempatmengenal konsep Lubuk Larangan. Pembagian kawasan aliran sungaimenjadi zona bebas tangkapan ikan dan zona larangan bagipenangkapan ikan didasari semakin menurunnya hasil tangkapanikan di sungai. Penetapan suatu daerah aliran sungai menjadi lubuklarangan dilakukan dalam kerangka memberi kesempatan kepadaikan di sungai untuk berkembang biak secara aman dan leluasa.Menurut Bustamir, ketika daerah aliran sungai dibagi menjadi zonabebas tangkapan dan zona larangan bagi penangkapan, maka secaraalamiah ikan akan cenderung mencari tempat yang aman. Singkatnya,penetapan lubuk larangan bagi masyarakat di Rimbang Balingdilandasi pentingnya melakukan konservasi ikan-ikan di sungaisehingga tetap terjaga sustainibilitasnya.
REDD: Antitesis Reboisasi?
88 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Lubuk Larangan bukan merupakan istilah yang khas hanya bagimasyarakat di sekitar Rimbang Baling. Di Sumatera Barat pun banyakditemukan tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi LubukLarangan. Namun terkadang ditemukan konsep “Lubuk Larangan”yang relatif berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Disebuah lokasi di sudut Danau Maninjau di Sumatera Barat misalnya,seseorang yang datang ke situ akan menemukan papan namabertuliskan penanda sebagai lokasi Lubuk Larangan. Ketika kamimenanyakan kepada seorang narasumber setempat diketahui bahwaLubuk Larangan yang dimaksudkan adalah larangan menangkapikan di kawasan tersebut, terkecuali dengan menggunakan pancingdan menaati ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan pihakpengelola kawasan tersebut.
Ini pada tingkat tertentu berbeda dengan konsepsi LubukLarangan yang dimaksudkan masyarakat di perkampungan sekitar
REDD: Antitesis Reboisasi?
89Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Lubuk Larangan di Rimbang Baling, merupakan zona larangan penangkapanikan, diterapkan akibat dari kecenderungan hasil tangkapan ikan yang semakinmenurun. sumber : scale up
kawasan Rimbang Baling. Lubuk Larangan yang dimaksudkanmasyarakat di tempat ini merupakan suatu kawasan di sungai yangdijadikan sebagai wilayah terlarang untuk diambil hasil ikannya dalamkurun waktu tertentu. Pelarangan ini biasanya ditetapkan berdasarkankeputusan ninik mamak di masing-masing kampung, yang kemudiandikuatkan dengan keputusan pemerintah desa bersangkutan. Di desaPangkalan Indarung bahkan penetapan kawasan Lubuk Larangandikuatkan oleh keputusan dari instansi pemerintah di tingkatkabupaten, yakni dinas perikanan kabupaten bersangkutan.
Perbedaan konsepsi pengelolaan Lubuk Larangan merupakansesuatu yang wajar, karena biasanya penetapan Lubuk Laranganberdasarkan pada kesepakatan bersama para ninik mamak di desabersangkutan. Pantang larang dan aturan main yang berlaku di LubukLarangan pun ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarat adatdi masing-masing komunitas adat. Lubuk Larangan menurutYusman, tokoh adat Batu Sanggan masuk dalam kategori adat yangdiadatkan. Artinya, merupakan keputusan adat yang bisa diterapkanmaupun ditiadakan, tergantung pada situasi dan kebutuhan. LubukLarangan bukan merupakan aturan baku yang harus ada di setiapkomunitas adat. Ini berbeda misalnya dengan aturan nikah-kawindalam sistem komunitas adat. Karena di masing-masing komunitasadat memiliki aturan atau adat istiadat mengenai nikah kawin.(Wawancara Yusman, 11/3/2010).
Meski posisi hukum penetapan Lubuk Larangan dalam sistemadat dikategorikan sebagai “adat yang diadatkan”, menariknyahampir di seluruh desa yang berada di tepian sungai yang berada dizona inti SM Rimbang Baling memiliki Lubuk Larangan. Beberapadesa di zona penyangga SM Rimbang Baling yang berada tepiansungai juga ditemukan memiliki Lubuk Larangan. Berdasarkanpengamatan dan informasi yang dikumpulkan saat penelitianlapangan ditemukan bahwa desa-desa yang memiliki lubuk laranganadalah Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Betalut,Aur Kuning, Terusan, Salo, Pangkalan Serai, Kota Lama, dan Ludai.
REDD: Antitesis Reboisasi?
90 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Beberapa desa memiliki satu kawasan Lubuk Larangan. Tapiditemukan pula desa yang memiliki kawasan Lubuk Larangan lebihdari satu lokasi. Desa Pangkalan Indarung misalnya memiliki empatlokasi Lubuk Larangan; yakni Lubuk Larangan Tepian MandiPangkalan Indarung, Lubuk Larangan Muara Kutun Jaya, dan LubukLarangan Batu Gadang/Kampung Terendam, dan Lubuk LaranganMuara Bubur. Desa Kuntu tidak memiliki Lubuk Larangan,meskipun menurut informasi Khalifah Bustamir dalam waktu dekatakan dilakukan musyawarah adat membicarakan penetapan LubukLarangan.
Menurut Bustamir dan Yusman, penetapan Lubuk Laranganmenjadi tren di perkampungan di zona inti Rimbang Baling semenjaktahun 1980-an. Ini terutama di dua desa tua yakni Desa Batu Sanggandan Aur Kuning. Bagi desa-desa yang baru terbentuk sebagai hasilpemekaran dua desa itu pada tahun 2003, maka Lubuk Larangan dimasing-masing desa ditetapkan ninik mamak setelah desa tersebutterbentuk. Di desa-desa yang berada di wilayah administratif KamparKiri Hulu, penetapan Lubuk Larangan ditetapkan berdasarkankeputusan ninik mamak yang dikuatkan dengan surat keputusanpemerintah desa bersangkutan.
Lubuk Larangan di Tepian Mandi Pangkalan Indarung ditetapkanpada tahun 1982 berdasarkan keputusan musyawarah adat, namunmasih sebatas kesepakatan lisan. Kemudian baru pada tahun 2007,ninik mamak di Pangkalan Indarung menerbitkan keputusan tertulistentang penetapan keputusan tersebut (Wawancara Iskandar, 12/3/2010). Penetapan ini seiring dengan penerbitan Surat keputusanKepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi KabupatenKuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang PengukuhanKelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga AdatPangkalan Indarung. Pada tahun yang sama Kepala Dinas PerikananKabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok PengawasMasyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung
REDD: Antitesis Reboisasi?
91Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Kecamatan Singingi Bidang Penangkapan Ikan dan Perlindungan.Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut keberadaanlembaga adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum.
Menarik dicermati bahwa desa-desa yang memiliki LubukLarangan adalah perkampungan yang secara geografis berada ditepian sungai. Daerah aliran sungai di Rimbang Baling yang dijadikanlokasi Lubuk Larangan adalah sungai Sebayang (Desa Gajah Betaluit,Batu Sanggan, Tanjung Belit, Terusan, Tanjung Beringin, dan AurKuning), Sungai Bio (Desa Muara Bio dan Ludai), dan SungaiSingingi (Desa Pangkalan Indarung). Menurut Bustamir dan Yusmantidak ada aturan khusus tentang lokasi yang dapat dijadikan sebagailokasi Lubuk Larangan. Namun berdasarkan diskusi dan pengamatanyang dilihat di lapangan, ditemukan beberapa pertimbangan yangbiasanya digunakan dalam penetapan sebuah lokasi sebagai LubukLarangan, antara lain yaitu :1) Lokasinya tidak jauh dari pusat pemukiman warga. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaanketentuan-ketentuan adat yang ditetapkan di Lubuk Larangan;
2) Daerah Aliran Sungai yang memiliki kedalaman yang cukupmemungkinkan untuk ikan berkembang biak. Sungai biasanyamerupakan perpaduan antara rantau dan lubuk. Rantau adalahdaerah dangkal yang berada di badan sungai. Sedangkan lubukmerupakan bagian-bagian dalam aliran sungai yang memilikikedalaman lebih. Lubuk Larangan biasanya ditetapkan di daerahaliran sungai yang memiliki bagian yang lebih dalam (lubuk);
3) Panjang aliran sungai yang dijadikan lokasi Lubuk Larangansekitar 300 s/d 1.500 meter. Artinya tidak semua daerah aliransungai di kampung bersangkutan ditetapkan sebagai kawasanlarangan bagi penangkapan ikan. Ini karena untuk pemenuhankebutuhan masyarakat setempat terhadap ikan sungai.
Mengamati pantang larang yang ditetapkan para ninik mamakdi masing-masing desa di kawasan Rimbang Baling terkait
REDD: Antitesis Reboisasi?
92 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pengelolaan Lubuk Larangan, ditemukan adanya keseragamanketentuan di setiap desa, tetapi juga ditemukan pantang larang yangberbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Keseragamanketentuan tersebut antara lain tentang larangan melakukan aktivitaspenangkapan ikan, kecuali pada masa panen lubuk larangan yangdilakukan setahun sekali; larangan mengambil bebatuan; danlarangan menebang pohon di kawasan lubuk larangan.
Box 2. Sanksi Pelanggaran Pantang Larang di LubukLarangan
Pada tahun 2007 aturan adat lubuk larangan Indarung telahdikukuhkan dalam surat keputusan Ninik Mamak secaratertulis. Keputusan adat tersebut dikeluarkan denganpertimbangan demi menjaga kelestarian sumber daya ikandi Sungai Singingi dalam wilayah Desa Pangkalan Indarung.Aturan adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat ninikmamak tersebut adalah :1. Setiap pelaku menangkap ikan di kawasan lubuk larangan
akan dikenakan sanksi Rp. 500.000 per ekor ikan;Pembeli atau penadah dikenakan sanksi Rp. 500.000 perorang;
2. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diprosesoleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secaraadat sesuai kemenakan mamak yang bersangkutan;
3. Apabila point 1 dan 2 dilakukan oleh ninik mamak,perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desadikenakan sanksi Rp. 1.000.000.
Sumber : Surat Keputusan Lembaga Adat Pangkalan IndarungTahun 2007 tentang Pengelolaan Lubuk Larangan Desa PangkalanIndarung
REDD: Antitesis Reboisasi?
93Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Namun dalam beberapa hal terdapat ketentuan yang berbedaantara satu desa dengan desa lainnya. Di desa Gajah Betaluitmisalnya, ninik mamak menetapkan agar perahu yang melewati desatersebut tidak melewati aliran sungai yang ditetapkan sebagai LubukLarangan. Di Pangkalan Indarung masyarakat dilarang menebangpepohonan yang ada sepanjang kawasan Lubuk Larangan. Perbedaanjuga terlihat dari keragaman sanksi yang ditetapkan bagi orang yangmenangkap ikan di Lubuk Larangan, setidaknya terlihat dari tingkatkelonggaran pelaksanaan sanksi terhadap orang yang melanggarpantang larang di Lubuk Larangan.
Masa-masa panen Lubuk Larangan yang dilakukan sekali dalamsetahun merupakan masa pesta di masing-masing kampung. DiPangkalan Indarung masa panen Lubuk Larangan biasanyamengundang pejabat di tingkat propinsi. Gubernur Riau Rusli Zainaldan Menteri PDT (Pemberdayaan Daerah Tertinggal) Lukman Edypada tahun 2008 lalu hadir saat panen Lubuk Larangan di PangkalanIndarung. Para perantau di masing-masing desa biasanya pulangkampung saat panen Lubuk Larangan. Acara panen biasanya diiringidengan upacara pesta kampung.
Hasil panen ikan di Lubuk Larangan biasanya dibagi-bagi untukpenduduk kampung bersangkutan. Hasilnya dinikmati bersama-sama.Tidak ada yang dikomersilkan untuk kepentingan individu, melainkanuntuk kepentingan publik seperti pembangunan mesjid, kepentinganperkumpulan organisasi remaja, kelompok perempuan dan lainsejenisnya. Iskandar menceritakan kepada kami bahwa hasil panenLubuk Larangan biasanya minimal sampai satu atau dua ton. Artinya,apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, hasil panen Lubuk Laranganminimal mencapai Rp.30 Juta. Kami mendapat cerita yang sama darimasing-masing desa mengenai hasil minimal panen Lubuk Larangan.
Di luar keuntungan kuantitatif tersebut pengelolaan aliran sungaidengan pola penetapan Lubuk Larangan menghasilkan keuntunganyang tak terkirakan bagi sustainibilitas pengelolaan sumber dayaalam di kawasan Rimbang Baling. Suhana, staf ahli anggota DPR
REDD: Antitesis Reboisasi?
94 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
RI Bidang Perikanan dan Kelautan memetakan dampak ekologis,ekonomi dan sosial budaya penetapan Lubuk Larangan PangkalanIndarung (Suhana, 2009:2-4).
Tabel 5. Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung
Secara ekonomi dampak penerapan Lubuk Larangan Indarungadalah : (1) Menjadi bagian masyarakat untuk meningkatkan rasacinta dan kepedulian terhadap pelestarian sumber daya hayatiperikanan; (2) Terbinanya kerukunan dan rasa kesetiakawanan sosialdi lingkungan masyarakat tempatan dan dijadikan tradisi adat dalamacara Mancuak/Panen sekali setahun, hasilnya dijadikan dana untukkegiatan-kegiatan sosial; dan (3) Terwujudnya lembaga sosialmasyarakat melalui kelembagaan adat dalam upaya pelestariansumber daya hayati perikanan.
Sementara itu secara sosial budaya dampak penerapan LubukLarangan tersebut adalah : (1) Dapat menyediakan sumber proteinbagi masyarakat Desa Indarung melalui ketersediaan ikan-ikan lokalyang bisa dipanen sekali dalam setahun; (2) Tersedianya sumber airbersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar; dan (3)Tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapatdijadikan sebagai ekowisata.
MencegahKerusakan
Lingkungan
Jalur hijau di sepan-jang daerah aliransungai (DAS) diper-tahankan Adanya la-rangan menangkapikan pada kawasantersebut, kecuali padasaat-saat tertentu (se-kali dalam setahun)
MenanggulangiKerusakan
Lingkungan
Bagi setiap pengrusaksumber daya perairankawasan Lubuk Lara-ngan oleh siapapunakan diberikan sanksisesuai hukum adat
MemulihkanKerusakan
Lingkungan
Untuk pemulihan ling-kungan ditetapkan ka-wasan Lubuk Lara-ngan sepanjang 1.500meter sebagai kawasankonservasi sumber da-ya ikan-ikan lokal
REDD: Antitesis Reboisasi?
95Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
3.1.3. STUDI KASUS IMPLEMENTASI REHABILITASIHUTAN DI RIMBANG BALING
1. Brief Review Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan LahanTim Peneliti CIFOR mendefinisi rehabilitasi hutan sebagai
kegiatan yang disengaja dengan tujuan regenerasi pohon, baik secaraalami maupun buatan di atas lahan berupa padang rumput, semakbelukar, atau wilayah tandus yang dulunya berhutan, dengan maksuduntuk meningkatkan produktivitas, penghidupan masyarakat, dan/atau manfaat jasa lingkungan (Dikutip dalam Adiwinata danMurniati, 2008:4). Kegiatan rehabilitasi hutan dimaksud mencakupintervensi teknis, pembaharuan atau pengaturan sosial ekonomi dankelembagaan (hak kepemilikan lahan, kebijakan, peraturanperundangan, dan pengawasan).
Departemen Kehutanan Indonesia menggunakan istilah-istilahkhusus untuk mendefinisikan usaha rehabilitasi berdasarkan statuskawasan atau lahan di mana sebuah proyek dilaksanakan, denganmembedakan antara istilah reboisasi/rehabilitasi hutan dengan istilahpenghijauan/rehabilitasi lahan. Reboisasi atau rehabilitasi hutanberkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan;sedangkan penghijauan atau rehabilitasi lahan adalah kegiatan yangbiasanya dilaksanakan pada lahan milik masyarakat di luar kawasanhutan negara (Adiwinata dan Murniati, 2008:4) melalui teknik vegetatifdan sipil teknis, dengan tujuan untuk memulihkan fungsi lahan tersebut.
Masyarakat umum cenderung merasa bahwa perbedaan antarareboisasi dan penghijauan hanya berkaitan dengan status hutan yangdi dalam atau di luar kawasan hutan negara dan mendefinisikanbatas wilayah yuridis dengan instansi pemerintah bersangkutan.Sebagai contoh, program Inpres ditetapkan baik di dalam maupundi luar kawasan hutan, namun terdapat dua instansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, yaitu Dinas Kehutanan Propinsi yangbertanggung jawab atas kegiatan reboisasi dan pemerintah kabupatenyang melaksanakan penghijauan.
REDD: Antitesis Reboisasi?
96 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 6. Aspek-aspek Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan
Sumber : Dikutip dari Ani Adiwinata, Murniati dan Lukas Rumboko,CIFOR, 2008:43.
AspekDefinisi
LingkupFokusKegiatan uta-ma dan tuju-annyaProgram/proyekcontoh
Reboisasi(Rehabilitasi Hutan)Usaha rehabilitasi arealhutan terdegradasi be-rupa lahan tandus,alang-alang atau semakbelukar dengan tujuanmengembalikan fungsihutan melalui pena-naman kembaliKegiatan rehabilitasidilakukan di dalam ka-wasan hutan• Memprioritaskan da-
erah aliran sungai dikawasan hutan lin-dung yang sangat per-lu untuk direha-bilitasi;
• Hutan produksi yangtidak dibebani hak
Menanami kawasan hutandengan spesies pohonhutan dan spesies tanamankehidupan yang berman-faat bagi masyarakat se-tempat; Program dilak-sanakan secara partisipatif,dengan tujuan untuk me-ngoptimalkan tutupanlahan dan memberikanmanfaat kepada masya-rakat setempatRehabilitasi lahan bekaspenebangan oleh limaperusahaan negara: In-hutani I hingga V. Inhutanimerupakan BUMN
Penghijauan(Rehabilitasi Lahan)
Usaha rehabilitasi lahan kritisdi luar kawasan hutan melaluiteknik vegetatif dan sipilteknis untuk mengembalikanfungsi lahan. Sipil teknismerupakan suatu teknikuntuk membangun fasilitaskonservasi tanah dan airKegiatan rehabilitasi dila-kukan pada lahan masya-rakat di luar kawasan hutan• Memprioritaskan areal/
lahan kritis milik ma-syarakat;
• Sejak tahun 1998, keter-libatan/ partisipasi ma-syarakat telah menjadibagian penting dari pen-dekatan yang digunakan
Mengembangkan petak per-contohan (demplot) denganharapan bahwa masyarakatsekitar dapat melihat danmeniru/melaksanakan pro-gram yang sama
Penghijauan Input Lang-sung ( PIL), PenghijauanAreal Dampak (PAD),Penghijauan Swadaya (PS)
REDD: Antitesis Reboisasi?
97Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Reboisasi difokuskan pada daerah aliran sungai (DAS) prioritasdi kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebanihak, dengan tujuan untuk meningkatkan tutupan hutan, danmelakukan pendekatan partisipatif dalam memberikan manfaatkepada masyarakat setempat. Untuk hutan produksi yang dibebanihak, tanggung jawab kegiatan rehabilitasi berada di tangan pihakyang memiliki hak dan membayar pajak berupa Dana JaminanReboisasi. Kegiatan reboisasi yang utama adalah penanaman hutankembali dengan jenis pohon hutan dan tanaman kehidupan, yangumumnya merupakan jenis serba guna.
Penghijauan difokuskan pada areal/lahan kritis yang diprioritaskanpada lahan masyarakat. Sejak tahun 1998 (awal Era Reformasi), keterlibatandan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pendekatanpelaksanaan penghijauan. Walaupun sejak tahun 1990-an, partisipasimasyarakat telah merupakan bagian dalam konsep pengembanganprogram rehabilitasi, namun dalam pelaksanaannya partisipasi dan peranmasyarakat tersebut masih terbatas. Oleh sebab itu, mulai tahun 1990,para ahli rehabilitasi di Indonesia cenderung mengkategorikan tahuntersebut dan tahun-tahun berikutnya sebagai masa transisi dari pendekatantop-down menjadi pendekatan partisipatif (1998).
2. Kebijakan Rehabilitasi Hutan di RiauPemaparan pada bab-bab sebelumnya memperlihatkan intensitas
degradasi hutan dan lahan di Propinsi Riau selama beberapa dekadeterakhir. Selama kurun waktu bersamaan pemerintah juga menerbitkankebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah guna mengurangitingkat degradasi hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan danlahan pada era otonomi daerah sedikitnya dilakukan dengan dua modelprogram, yakni proyek DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – DanaReboisasi) yang dimulai pada tahun 2001, dan program GN-RHL(Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang mulaidiluncurkan pada tahun 2003. Berikut ini adalah data anggaran danaproyek rehabilitasi hutan dan lahan di Propinsi Riau.
REDD: Antitesis Reboisasi?
98 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 7. Deskripsi Anggaran Dana Proyek Rehabilitasi Hutandi Riau
Tahun
2001
2002
2003
2004
Nilai Proyek
81,7 miliar
113,2 miliar
118 miliar
68 miliar
Keterangan
Termasuk dana di wilayah Kepulauan Riau.Status dana: DAK-DR (Dana AlokasiKhusus – Dana Reboisasi)Termasuk dana di wilayah Kepulauan Riau.Status dana: DAK-DR (Dana AlokasiKhusus – Dana Reboisasi)Angka tersebut meliputi anggaran untukwilayah Kepulauan Riau. Sumber dana:DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – DanaReboisasi). Pendistribusian dana antara lainuntuk setiap kabupaten/kota menerimadana sebagaimana berikut: Pekanbarumenerima sebesar Rp. 2,0 Miliar, Kamparmenerima Rp. 9,0 miliar, Indragiri Hulumenerima Rp. 8,0 miliar, Indragiri Hilirmenerima Rp. 6,0 Miliar, Rokan Hulumenerima Rp. 10,0 miliar, Rokan Hilirmenerima Rp. 9,2 miliar, Kuantan SingingiRp.10,3 menerima miliar, Pelalawanmenerima Rp. 13,1 miliar, Siak Rp. 9,2menerima miliar, Bengkalis menerima Rp.8,8 miliar, dan Dumai menerima Rp. 2,6miliarDana rogram GNHRL tahun 2003/2004.Perincian penggunaan dana tersebutsebagaimana berikut : sebesar Rp. 19,1miliar dikelola BPDAS Indragiri Rokan;BKSDA Riau mengelola sebesar 8,7 miliar,Dinas Kehutanan Riau sebesar Rp. 1,6miliar, Dinas Kehutanan Kampar sebesarRp. 21,2 miliar, Dinas Kehutanan RokanHulu sebesar Rp. 3,3 Miliar, DinasKehutanan Kuantan Singingi sebesar Rp. 6,3Miliar, Dinas Kehutanan Pelalawan sebesarRp. 1,5 Miliar dan Dinas Kehutanan Siaksebesar Rp. 2,9 Miliar
REDD: Antitesis Reboisasi?
99Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 8. Perkembangan Kegiatan Penanaman ProgramGerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006
Sumber : Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2007
Grafik 4. Perbandingan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauandi Propinsi Riau dengan Dana DAK-DR Tahun 2003
Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Bangunan Konservasi TanahProgram Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006
Tahun Dam Pengendali Dam Penahan Gully Plug Embung Air Jumlah (Ha) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
2003 - 5 - - 52004 - - - - 02005 - - - - 02006 - - - - 0
Total - 5 - - 5
Sumber : Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2007
REDD: Antitesis Reboisasi?
100 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Data di atas memperlihatkan bahwa selama kurun 2003-2006,sebanyak 27,533 ha lahan yang terdegradasi ditanami kembali; terdiridari 16,512 ha merupakan kegiatan reboisasi (rehabilitasi hutan),10,894 ha penanaman dilakukan di lokasi berstatus kawasan hutanrakyat, 42 ha penanaman dilakukan di kawasan berstatus hutan kota,94 ha proyek penanaman dilakukan di kawasan hutan bakau. Tahun2004 tercatat sebagai tahun yang paling banyak dilakukan rehabilitasihutan, yakni di area seluas 13,000 ha.
Tabel 10.Distribusi Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi(DAK-DR) dan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi(DBH-DR) di Propinsi Riau Tahun 2001 s/d 2009
Tahun Alokasi DAK-DR dan DBH-DR (dalam Rp.)
2001 81,673,000,000.002002 65,463,000,000.002003 100,495,000,000.002004 100,573,000,000.002005 86,092,000,000.002006 16,686,000,000.002007 10,262,000,000.002008 10,338,000,000.002009 15,554,000,000.00Total 487,136,000,000.00
Sumber : Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK.02/2001;471/KMK.02/2002; 480/KMK.02/2003; 605/KMK.02/2004; 611/KMK.02/2005; 14/PMK.02/2006; 40/PMK.07/2007; 158/PMK.07/2007; 195/PMK.02/2008. (Data dikutip dari Christopher Barr,2010:38-39).
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Ir. SyuhadaTasman dalam sebuah wawancara dengan media lokal padaacara pencanangan gerakan nasional rehabilitasi hutan danlahan (GN-RHL) , yang d i l aksanakan d i r uang h i j au
REDD: Antitesis Reboisasi?
101Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
gubernuran mengatakan bahwa anggaran dana GN-RHL tahun2004 sebesar Rp 68 miliar untuk merehabilitasi hutan danlahan seluas 16.105 ha yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota diPropinsi Riau. Sasaran kegiatan program GN-RHL di PropinsiRiau pada tahap awal akan dilaksanakan pada Daerah AliranSungai (DAS) Kampar sebagai salah satu DAS Prioritaspertama di Propinsi Riau.
3. Potret Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diRimbang BalingSalah satu lokasi proyek rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan
Rimbang Baling dilakukan melalui program GN-RHL (GerakanNasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) anggaran tahun 2003,dilakukan di dua desa yaitu Desa Kuntu dan Desa PangkalanIndarung. Desa yang disebutkan pertama berada di wilayahadministratif Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar,sementara desa yang disebutkan kedua berada di KecamatanSingingi, Kabupaten Kuansing. Di desa Kuntu, proyek rehabilitasidilakukan dengan pembangunan hutan rakyat, sementara diPangkalan Indarung dilakukan dengan pembangunan perkebunanhutan karet.
Pada tahun 2004 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp68 miliar untuk merehabilitasi hutan dan lahan seluas 16.105 hayang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, antara lain dikedua desa di kawasan Rimbang Baling. Dasar hukum pelaksanaanproyek rehabilitasi hutan dan lahan tersebut dituangkan dalamPeraturan Menteri Kehutanan P.25/Menhut/II/2003 tanggal 8 Mei2003 tentang pedoman penilaian pelaksanaan GN-RHL Tahun 2003dan 2004; dan Surat Keputusan Nomor : 449/KPTS/BKSDA-1/III-I/2004 tanggal 4 Februari 2004, tentang pengesahan rencanaoperasional kegiatan pembinaan dan peningkatan usaha pencegahandan pemulihan kerusakan hutan, tanah, dan air GN-RHL BKSDARiau tahun 2004. Di kawasan konservasi, pemerintah menargetkan
REDD: Antitesis Reboisasi?
102 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
rehabilitasi di lokasi seluas 4.150 ha, salah satunya kawasan RimbangBaling, tepatnya di dua desa yang disebutkan di atas.
Tabel 11. Distribusi Lokasi Pelaksanaan Proyek GN-RHL diRiau Tahun 2004
Kabupaten/ Luas Areal KeteranganKota Proyek (Ha)
Rokan Hulu 1.125 Kawasan Kecamatan Tandundan Kota Ranah
Kampar 6.625 Kawasan Kecamatan XIIIKoto Kampar, Bangkinang,Kampar Kiri, Kampar KiriHulu, Kampar Kiri Hilir,Tambang dan KecamatanKampar. Di Kampar KiriHulu, salah satu desa yangmenjadi lokasi proyekadalah Kuntu
Kuntan Singingi 2.200 Kawasan Petai, Logas, Situgal,Pangkalan Indarung(Kecamatan Singingi Hulu),dan Sompu
Pelalawan 750 Kawasan Kecamatan UkuiSiak 1.000 Kawasan Kecamatan CengalPekanbaru 225 Kawasan Rumbai, Taman
Hutan Rakyat Sultan SyarifQasyim
Hutan Konservasi 4.150 Antara lain Suaka MargasatwaRimbang Baling
Sumber : Riau Online http://www.riau.go.id/index.php?mod=-isi&id_news=2260
REDD: Antitesis Reboisasi?
103Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
A. Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri HuluKuntu salah satu dari empat desa yang menjadi lokasi program
GN-RHL di kawasan koservasi Rimbang Baling. Luas areal proyekdi Kuntu sekitar separuh dari total areal proyek rehabilitasi padatahun tersebut. Nilai proyek rehabilitasi hutan dan lahan di DesaKuntu sebesar 8.3 miliar. Tiga desa lainnya yang menjadi lokasiproyek berada di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni di KecamatanSingingi meliputi desa Pangkalan Indarung, Pulau Padang, danLogas. Tidak ditemukan data nilai proyek rehabilitasi hutan danlahan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun tersebut.
Proyek dipimpin oleh Maulana Harahap dan Totoh Haseantoroselaku bendaharawan. Keduanya tercatat sebagai staff BBKSDAPropinsi Riau. Penetapan Maulana Harahap sebagai pimpinan proyekberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan setelahberkoordinasi dengan BKSDA Propinsi Riau. Penetapan pelaksanankegiatan dilakukan dengan penunjukan langsung, atau tanpamekanisme pentenderan. Selaku pimpinan proyek, Maulanamelibatkan beberapa pegawai BBKSDA yang terlibat sebagai timteknis. Dalam pelaksanaannya, Maulana juga membentuk TimPengawas proyek di lapangan, anggotanya terdiri dari Jafri (tokohpemuda Kuntu), Khalifah Bustamir (tokoh adat Kuntu) dan satulagi orang lagi yang juga berasal dari warga desa Kuntu.
Metode pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan dibawahpayung GN-RHL semestinya didasarkan pendekatan partisipatif,dengan melibatkan warga tempatan. Namun dalam pelaksanaannyadi Kuntu, informan yang diwawancarai mengaku bahwa wargaKuntu tidak dilibatkan dalam program penanaman, kecuali beberapaorang sebagai pimpinan lapangan (Pinlap) dan Pengawas Proyek.Menurut Bustami, Pinlap pun hanya satu orang yang aktif melakukanpekerjaannya, lainnya tidak aktif. Tukang tanam tidak direkrut dariwarga Kuntu. Maulana Harahap selaku pimpinan proyek lebihmemilih merekrut tukang tanam dari warga transmigran asalkampung sebelah. SKPC nama blok lokasi desa transmigrannya.
REDD: Antitesis Reboisasi?
104 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tidak diketahui pasti alasan Maulana Harahap tidak memilih wargaKuntu sebagai tukang tanam. Tapi biasanya hal ini terkait denganupah tanam yang diminta oleh warga transmigran yang beretnis Jawaini relatif lebih rendah dari upah tanam yang ditawarkan penduduktempatan asli melayu yang notabene mayoritas warga Kuntu.
Dalam perjalanannya proyek ini bermasalah secara hukum.Tanggal 21 Mei 2008, Maulana Harahap dan Totoh Haseantoroditahan pihak kepolisian atas sangkaan tidak dapat mempertang-gungjawabkan laporan penggunaan dana proyek GN-RHL tersebut.Dana habis, tapi dia tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaranatau pemanfaatan dana. Di pengadilan negeri Pekanbaru, keduanyadituntut hukuman tujuh tahun penjara. Tanggal 23 Januari 2009,Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan vonis empat tahunpenjara untuk Maulana Harahap dan Totok Haseantoro. Maulanadan Totok sekarang sedang menjalani hukuman karena terbukti tidakdapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana GN-RHL, dandinilai tidak bisa membuktikan apakah pekerjaan rehabilitasi hutandan lahan dilakukan atau tidak di lapangan.
Patut diakui bahwa di lapangan Maulana memang telah bekerjaatau melakukan kegiatan rehabiliasi hutan dan lahan di Kuntu. Meskipekerjaan yang dilakukan tidak sempurna dan tidak membuahkanhasil maksimal seperti yang ditargetkan. Menurut Bustamir, MaulanaHarahap tidak bisa membuktikan apakah di lapangan pekerjaanrehabilitasi hutan dan lahan tersebut dilakukan atau tidak; karenadia sendiri tidak pernah melihat langsung pelaksanaan kegiatan olehtimnya di lapangan. Maulana tidak pernah masuk ke dalam lokasiproyek. Dia memang pernah sekali datang ke Kuntu melihat lokasipengumpulan bibit, tapi hanya sampai di situ dan tidak melihatlangsung aktivitas penanaman di dalam hutan. Artinya kontrolterhadap pelaksanaan kegiatan sangat longgar dan lemah.
Menurut Jafri dan Bustamir, masalah lain yang melingkupi proyekGN-RHL di Kuntu adalah masalah bibit yang masih terlalu keciluntuk ditanam di dalam hutan. Lebih parahnya lagi, sebagian besar
REDD: Antitesis Reboisasi?
105Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
bibit bahkan tidak ditanam. Ada yang bibit dikubur, demikian istilahyang digunakan Jafri untuk mengatakan bahwa bibit itu hanya dionggok di suatu lokasi di dalam hutan, tanpa ditanam. Meskipunbibit tersebut masih kecil, sebenarnya kalaupun ditanam pasti adayang hidup, meski hanya separuh. Tapi ini tidak berarti bahwa bibittersebut tidak ditanam sama sekali. Di lokasi yang tidak jauh darijalan, memang dilakukan aktivitas penanaman, tapi di tempat-tempatyang jauh di dalam hutan, bibit hanya dionggok atau tidak ditanam.Masalah lainnya adalah, menurut beberapa informan, Maulanahingga saat ini tidak menunaikan tanggungjawabnya, dengan belummembayar upah kepada warga yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.Bustamir dan Jafri selaku pengawas mengaku belum dapat upahyang dijanjikan Maulana sebesar Rp.18 juta untuk tiga orangpengawas yang telah bekerja selama tiga bulan (Wawancara Jafridan Bustamir, 3/3/2010).
Pengamatan atas lokasi proyek GN-RHL di Kuntu saat ini,setelah sekitar enam tahun pelaksanaan memang belummemperlihatkan hasilnya. Ada ditemukan beberapa tanaman yanghidup, tapi mayoritas tanaman mati. Proyek rehabilitasi hutan danlahan di Kuntu secara umum dapat disimpulkan sebagai proyekgagal. Menurut Bustamir (wawancara 3/3/2010), kegagalandikarenakan beberapa hal :1) Manajemen pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal.
Pengelolaan dana dan pengorganisasian kegiatan merupakanpangkal masalah kegagalan proyek GN-RHL di Kuntu;
2) Bibit yang ditanam terlalu kecil, bahkan sebagian bibit ditemukantidak ditanam. Perguruan tinggi yang melaksanaan pembibitandinilai kurang cermat karena tidak mempertimbangkan antarakondisi lahan dengan spesifikasi bibit;
3) Tidak melibatkan warga dan organisasi masyarakat setempatsebagai mitra utama dalam pelaksanaan proyek. Akibatnya, wargamenjadi permisif dengan aktivitas rehabilitasi hutan dan lahandi kawasan tersebut;
REDD: Antitesis Reboisasi?
106 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
4) Tidak adanya insentif ekonomi yang dapat merangsangpartisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahandi Kuntu. Masyarakat Kuntu yang ditemui mengaku bahwaproyek GN-RHL di desa mereka tidak menimbulkan dampakekonomi bagi warga tempatan, baik saat proyek dilaksanakanmaupun setelahnya;
5) Tidak adanya pengawasan setelah aktivitas penanaman selesaidilakukan.
Menurut Bustamir, berdasarkan kondisi alam dan karakterpertanahan di Kuntu, sebetulnya untuk melakukan penghijauan tidakcukup sulit dilakukan, sejauh semua pihak memberikan dukunganatas penghijauan di kawasan konservasi tersebut. Ada beberapa halyang menurutnya perlu diperhatikan dalam melakukan rehabilitasihutan dan lahan :1) Melakukan moratorium log ging. Kawasan Rimbang Baling
merupakan hutan tropis, karena itu apabila lahan dibiarkan, hutanpun akan tumbuh secara alamiah;
2) Tindak tegas semua sawmill tanpa izin yang ada di sekitar kawasanRimbang Baling. Masyarakat menebang hutan karena ada sawmillyang menampung hasil penebangan. Dengan satu sawmill, makaartinya ratusan kubik perhari kebutuhan kayunya;
3) Upayakan ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat.Ekonomi masyarakat saat ini bergantung iklim, karena mayoritasmasyarakat adalah petani karet. Kalau musim penghujanmasyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, sehinggabisnis perkayuan ilegal menjadi pilihan yang tidak terelakkan.Karena itu, apabila ada proyek REDD, dananya harus diberikanjuga ke masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkankesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
4) Kalau ada proyek penanaman atau rehabilitasi hutan dan lahanhendaknya melibatkan masyarakat. Perkuat kelembagaan di desauntuk mengawal hutan. Kelembagaan adat di desa harus ditata
REDD: Antitesis Reboisasi?
107Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
ulang. Buat komunitas adat yang melibatkan generasi muda.Karena merekalah yang di lapangan mampu mengawal hutan.Kasus Maulana contoh praktek pelaksanaan proyek yang tidakmelibatkan masyarakat;
5) Tingkatkan kualitas manajemen pelaksanaan kegiatan. Jenistanaman untuk proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntupada kasus kemarin memang cocok, tapi bermasalah dalampelaksanaan, karena bibit tak memenuhi spesifikasi umur, danbahkan di lapangan sebagian bibit tidak ditanam.
B. Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan SingingiRehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung dilaksanakan di area
bekas penebangan HPH PT. National Timber. Hutan alam sudahditebang sejak perusahaan ini mendapatkan izin HPH sekitar awal1990-an. Kondisi lahan ketika proyek rehabilitasi lahan dilakukan,merupakan lahan tidur yang sudah menjadi semak belukar. Sudahbelasan tahun lahan ini terlantar setelah perusahaan tersebutmenyelesaikan penebangan. Masyarakat mengklaim bahwa lahanbekas tebangan yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan, statuskepemilikan kembali ke masyarakat.
Proyek GN-RHL di Pangkalan Indarung dilakukan tahun 2003.Lokasi dilakukan di Sungai Bubur, sekitar 15 km dari pusatpemerintahan desa Pangkalan Indarung. Pada tahun yang sama,proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kuantan Singingidilakukan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Singingi (PangkalanIndarung, Pulau Padang, dan Logas), Kecamatan Singingi Hilir(Petai), Kecamatan Logas Tanah Darat (Situgal), dan KecamatanHulu Kuantan Tengah (Sompu); dengan total luas areal yangdirehabilitasi sebesar 2.200 ha. Menurut Syuhada Tasman, KepalaDinas Kehutanan Propinsi Riau, proyek ini di lapangan di ketuaioleh Bupati/Walikota sedangkan dalam pelaksanaannya dikendalikanoleh tim pengendali hutan dan lahan tingkat Propinsi Riau(www.riau.go.id/index.php?mod=isi&id_news=2260).
REDD: Antitesis Reboisasi?
108 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Masyarakat membentuk tiga kelompok tani. Kelompok tanidibentuk dari unsur masyarakat berdasarkan koordinasi pimpinandesa dengan pelaksana proyek. Organisasi dibentuk secara ad hoc,beberapa waktu sebelum pelaksanaan proyek. Menurut Iskandar,tokoh masyarakat, organisasi kelompok tani ini dibuat secaramendadak, beberapa saat sebelum pelaksanaan proyek, untukkepentingan pencairan dana. Satu orang membuka satu hektar lahan.Ada seratus orang peserta di tiga kelompok tersebut. Masing-masingmendapat bagian satu hektar. Artinya proyek rehabilitasi lahan diPangkalan Indarung dilakukan pada lahan 100 Ha, dari 2.200 haproyek rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan di kabupatentersebut (Wawancara Iskandar, 21/04/2010).
Pelaksanaan proyek dilakukan dengan pendekatan partisipatif.Masyarakat terlibat dalam proses pengondisian lahan sehinggamemungkinkan untuk ditanami bibit karet. Penanaman bibit karetdilakukan masyarakat, tanpa mendapat upah tanam. Tapi masyarakatmendapatkan upah dari pelaksanan proyek atas pembersihan/penebangan semak belukar (imas tumbang) sehingga memungkinkanuntuk ditanami bibit karet. Penebangan semak belukar dilakukanoleh masing-masing masyarakat dan dihargai Rp. 1.000.000 untuksetiap satu hektar lahan.
Rehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung, dilakukan denganpenanaman bibit karet perkawinan silang (karet okulasi). Pemilihanspesifikasi tanaman dengan bibit karet didasarkan pertimbanganbahwa karet merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakatdi Pangkalan Indarung. Meski jenis bibit karet yang ditanamtergolong baru bagi masyarakat, karena biasanya masyarakatmenanam karet kampung, tetapi jenis bibit tanaman rehabilitasi lahantersebut tidak dipersoalkan oleh masyarakat.
Penanaman dilakukan oleh masing-masing pemilik (atau yangmendapat jatah) lahan. Tidak ada upah penanaman karet. Setelahpenanaman selesai, kelompok tani tersebut dibubarkan. Tidak adaperawatan secara kolektif. Masing-masing pemilik lahan bertanggung
REDD: Antitesis Reboisasi?
109Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
jawab atas pemeliharaan tanaman karet tersebut. Tetapi masalahnya,lokasi lahan yang jauh (15 km dari pemukiman) menjadikan kontroldan perawatan berlangsung secara kurang maksimal. Hama karet,serangan babi hutan, merupakan masalah utama yang dihadapimasyarakat. Selama proyek berlangsung, Iskandar mengaku bahwapenyuluhan dari pemerintah masih relatif kurang, sehingga warga kurangterampil dalam pemeliharaan dan perawatan kebun karet tersebut.
Menurut Iskandar, proyek rehabilitasi lahan di PangkalanIndarung dengan membangun perkebunan karet masyarakat, tingkatkeberhasilannya rata-rata mencapai 50-70 persen di setiap hektarlahan. Ini secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilanproyek rehabilitasi lahan di desa sekitar kawasan Pangkalan Indarungini relatif berhasil. Tapi meski demikian, patut juga dikemukakanhal-hal yang menjadi kendala adalah tidak maksimalnya pelaksanaanproyek tersebut. Pertama, lokasi proyek yang jauh mengakibatkanmasyarakat pemilik lahan kesulitan melakukan kontrol danpemeliharaan atas lahan bersangkutan. Kedua, kelompok tani yangdibentuk secara mendadak dan dibubarkan setelah proyek selesai,mengakibatkan kontrol terhadap program pasca selesainyapenanaman kurang terkoordinasi dengan baik.
4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan KegagalanPelaksanaan proyek GN-RHL di Kuntu (Kabupaten Kampar) dan
di Pangkalan Indarung (Kabupaten Kuansing) memperlihatkan duahal yang pada kadar tertentu berujung pada muara yang berbeda.GN-RHL di Kuntu merupakan proyek gagal, sementara di PangkalanIndarung dinilai berhasil secara relatif. Indikator kegagalan proyekrehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu setidaknya dapat dilihat dariminimnya tingkat hidup tanaman, manajemen pengelolaan proyekyang menimbulkan masalah hukum bagi pelaksana proyek, dan tidakadanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan proyek.
Proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu memperlihatkanadanya praktek penyimpangan penggunaaan dana reboisasi. Temuan
REDD: Antitesis Reboisasi?
110 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
penyimpangan dana reboisasi merupakan penjelas kenapapenanaman lahan kritis di kawasan ini dan tempat lainnya di Riautidak pernah membuahkan hasil seperti yang diharapkan.Pengelolaan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntumerupakan salah satu contoh yang menggambarkan umumnyapengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan di propinsi ini. Karena itudapat dimengerti —meski diakui sebagai respon yang sangatberlebihan— ketika para aktivis LSM meminta agar proyek-proyekrehabilitasi hutan dan lahan di Riau dihentikan sementara.
Box 3.Proyek Rehabilitasi Hutan Riau Diminta Distop
Chaidir Anwar Tanjung – detikNewsRabu, 30/11/2005 15:36 WIB
Jakarta - Saban tahun Propinsi Riau menerima dana GerakanRehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sebesar Rp 64 miliardari Pemerintah Pusat. Tapi dalam pelaksanaan proyek Gerhanbanyak yang salah sasaran. Proyek itu pun dituntut dihentikansementara. Hal itu disampaikan Direktur Jaringan KerjaPenyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Zulfahmi kepadadetikcom saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Angsa,Pekanbaru, Rabu (30/11/2005).
Tahun 2004 lalu, Pemprov Riau menerima Rp 64 miliar untukmerehabilitasi lahan kritis seluas 17.240 hektar. Tapi ternyatadalam pelaksanaannya, kondisi lahan kritis yang dimaksudbanyak yang tidak tepat sasaran. Kasus seperti itu, kata Zulfahmi,misalnya terjadi di sekitar kawasan hutan Koto Panjang,Kabupaten Kampar. “Selama ini polanya selalu saja lahan yangakan direhalibitasi terlebih dahulu kayu dihabiskan. Selanjutnyabaru ada penanaman pohon kembali,” kata Zulfahmi.
REDD: Antitesis Reboisasi?
111Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Menurut Zulfahmi, seharusnya kayu-kayu di lahan yangakan direhabilitasi dibiarkan tumbuh secara alami. Baruselanjutnya, di lahan kritis itu bisa disisipkan penanamampohon kembali. “Akan lebih baik, di sejumlah kawasan kritis,hasil kayunya dibiarkan tumbuh secara alami tanpa harusmenghabisinya. Jelas sistem yang selama ini diterapkan kurangmaksimal,” kata Zulfahmi. Di samping sistem proyek Gerhanyang mesti ditinjau ulang, menurut Zulfahmi, tidak kalahpentingnya pemerintah juga harus meninjau ulang lokasi yangakan dikerjakan.
Selama ini proyek Gerhan terkesan asal jadi dan penempatanproyek miliran itu kurang tepat sasaran. “Sebaiknya pelaksanaanproyek Gerhan dihentikan sementara menunggu sampai finalhasil Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yangditetapkan pemerintah Propinsi Riau. Sebab, dari sana nantinyaakan jelas, lokasi mana saja yang ditetapkan sebagai kawasankritis,” katanya. Selama ini, lanjut Zulfahmi, proyek Gerhan di-laksanakan sekedar memenuhi kuantitas tanpa melihat ku-alitasnya. Lokasi yang dijadikan proyek selama ini sangat rawanakan terjadi perubahan kawasan fungsi hutan itu sendiri. (iy/)
Sumber : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/11/tgl/30/time/153622/idnews/489502/idkanal/10.
Para aktivis LSM menuntut agar pengungkapan secara transparandan tuntas terhadap korupsi dana reboisasi di semua daerah dikabupaten/kota di Riau karena kondisi hutan alam Riau yang semakinkritis, dan telah secara nyata menimbulkan dampak yang merugikanbagi masyarakat. Menurut para aktivis LSM, kerugian yang palingnyata akibat eksploitasi hutan yaitu bencana banjir dan kabut asap,yang pada gilirannya berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah/Negara karena harus selalu menyediakan alokasi
REDD: Antitesis Reboisasi?
112 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
untuk rehabilitasi infrastruktur fisik dan subsidi bagi masyarakatkorban (Sumber: Ahmad Zazali, 2006, dokumen tidak dipublikasikan).
Berbeda dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan diKuntu, pengelolaan proyek yang sama di Pangkalan Indarungmemperlihatkan keberhasilan yang relatif. Beberapa yangdiwawancarai mengatakan bahwa mereka mengambil manfaat dariadanya program tersebut. Spesifikasi tanaman yang dipilih yaknijenis karet yang sudah akrab di masyarakat merupakan salah satufaktor yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalammendukung pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan di desatersebut. Iskandar, dalam sebuah wawancara mengaku bahwa meskitidak berhasil seratus persen, pohon karet yang ditanam kini sudahtumbuh. Kendala yang dihadapi masyarakat, menurut Iskandar,adalah lokasi proyek yang menurutnya jauh dari lokasi pemukimanmereka (sekitar 15 km), sehingga menyulitkan mereka melakukanpengawasan secara aktif. Di luar kendala tersebut, keterlibatan aktifmasyarakat dalam proses penyiapan lahan, penanaman bibit, danpengawasan merupakan indikator yang dapat digunakan untukmenilai keberhasilan relatif dari proyek rehabilitasi hutan dan lahandi Pangkalan Indarung (Wawancara Iskandar, 12-13 Maret 2010).
3.2. STUDI POLITIK HUKUM PERLINDUNGANHUTAN DARI REFORESTASI : MENYIGIKEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DANLAHAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT
3.2.1. Kebijakan Kehutanan dan GN-RHL Di Sumatera Barat
1. Kondisi Kehutanan dan Kebijakan Kehutanan di SumateraBaratLuas hutan Sumatera Barat 4.228.730 ha. Luasan ini terbagi ke dalam
REDD: Antitesis Reboisasi?
113Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Hutan Suaka Alam Wisata seluas 846.145 ha, Hutan Lindung seluas910.533 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 247.385 ha, Hutan ProduksiTetap seluas 434.568 ha, Hutan Produksi Konversi 161.655 ha, danareal penggunaan Lain seluas 1.628.444 ha. Tiga besar Kabupatenpemilik hutan produksi secara berturut-turut adalah KabupatenKepulauan Mentawai, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (sebelumnyatermasuk juga Dharmasraya yang kini sudah dimekarkan menjadikabupaten sendiri) dan Solok (sebelumnya juga meliputi kabupatenSolok Selatan yang kini pun sudah menjadi kabupaten sendiri).
Pada tahun 2003, tercatat ada 9 perusahaan yang mengantongiIUPHHK dengan total luas lahan yang diusahakan sebesar 397.667 ha.Sembilan perusahaan tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (83.330ha), PT Simber Surya Semesta (79.000 ha), PT. Duta Maju Timber (47.000ha), PT. Andalas Merapi Timber (28.840 ha), PT. Bhara Union (33.700ha), Koperasi Andalas Madani (49.650 ha), PT. Bukit Raya Mudisa (28.617ha), PT. Inhutani IV (40.855 ha) dan PT. Rimba Swasembada Semesta(6.675 ha) (Statistik Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, 2003).
Selain 9 perusahaan tersebut yang memanfaatkan hutan alam didalam kawasan hutan produksi, dalam tahun 2003 beberapakabupaten/kota di Sumatera Barat juga mengeluarkan perizinan dibidang kehutanan hasil hutan kayu. Kabupaten Pesisir Selatanmengeluarkan 3 izin IPKTM dengan luas lahan 49,6 ha. KabupatenSawahlunto/Sijunjung mengeluarkan 3 izin IPK kepadaPRIMKOPPOL Resort Sawahlunto/Sijunjung dengan total luas1.650 ha. Kabupaten Solok mengeluarkan izan IPK kepada KSUTanjung Balit Sumiso seluas 530 ha. Kabupaten 50 Kotamengeluarkan izin IPHHK kepada CV. Sinar Asia seluas 500 ha.Kabupaten Pasaman mengeluarkan 5 izin IPKR dan 1 izinpemanfaatan limbah kayu dengan luas lahan 2.791. KabupatenKepulauan Mentawai mengeluarkan 12 izin IPK dengan luas totallahan 12.861 ha. Dari izin-izin IPK ini setidaknya dalam periodesatu tahun, 18.381 ha lahan di luar kawasan hutan akan mengalamideforestasi dan degradasi. Pada periode yang sama tercatat 10.042
REDD: Antitesis Reboisasi?
114 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
SKSHH telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota. KabupatenKepulauan Mentawai dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjungmerupakan kabupaten yang paling banyak mengeluarkan SKSHH(Statistik Kehutanan sumatera Barat, 2003).
Dalam prakteknya izin-izin IPK selalu menjadi alat legal untukmerusak hutan dan tutupan lahan. Beberapa pemegang IPK bisamemperoleh izin, tanpa ada harus ada izin jenis usaha yang maudikembangkan di lokasi yang dilakukan land clearing.
Jika dibagi ke dalam DAS, wilayah hutan Sumatera Barat terbagike dalam 30 DAS, yaitu DAS Air Bangis, Batahan, Sikabau, Sikilang,Pasaman, Rokan, Kinali, Masang, Kampar, Antokan, Gasan Gadang,Kinara, Manggung, Anai, Arau, Tarusan, Bayang, Lumpo, Painan,Taratak, Surantih, Kambang, Lakitan, Palapah, Air Haji, Indra Pura,Silaut, Batang Kuantan, Batang Hari dan Mentawai (RencanaKegiatan Hutan dan Lahan BP DAS Agam Kuantan, 2003). Dari30 DAS itu, DAS Rokan merupakan DAS terluas.
Pada saat GN-RHL dimulai pada tahun 2003, di Sumatera Baratterdapat lahan kritis seluas 214.580 ha (Rencana Kegiatan Hutan danLahan BP DAS Agam Kuantan, 2003). Sebanyak 77.090 ha terdapatdi dalam kawasan hutan dan 137.490 ha berada di luar kawasan hutan.Dari 43 DAS yang ada, DAS Batang Kuantan merupakan DAS denganluasan lahan kritis terluas, yaitu sebesar 87.760 ha.
Jika dilihat angka luasan yang ada, luas lahan kritis di Sumatera Baratlebih banyak terdapat di luar kawasan hutan. Tidak diperoleh data yangdapat mengkonfirmasi apakah lahan-lahan kritis di luar kawasan hutantersebut berada pada daerah-daerah hulu DAS, yang kalau berada di daerahhulu-hulu DAS, semestinya luasan rencana GN-RHL lebih banyakdilakukan di luar kawasan hutan dengan membangun hutan rakyat.
2. Target RHL dalam GN-RHL di Sumatera BaratSampai tahun 2007/2008, melalui GN-RHL direncanakan seluas
74.736 ha hutan dan lahan di Sumatera Barat akan terrehabilitasi. Jumlahluasan tersebut akan tersebar sebanyak 39.054 ha di dalam kawasan
REDD: Antitesis Reboisasi?
115Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
hutan dan 35.682 ha di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutanmeliputi hutan rakyat yang direncanakan akan terbangun sebanyak34.612 ha, hutan kota seluas 325 ha, hutan mangrove seluas 270 ha,Green Belt seluas 250 ha, Model TUL seluas 25 ha, dan hutan pantaiseluas 200 ha. Jumlah hutan dan lahan terrehabilitasi seluas 74.736tersebut secara bertahap direncanakan akan dicapai pada tahun I seluas29.401 ha (39,3%), tahun II seluas 10.000 ha (13,38%), tahun III seluas11.250 ha (15,05%), tahun IV seluas 1.450 ha (1,94%), dan tahun IVseluas 22.635 ha (30,28%). Sebaran luasan target GN-RHL perKabupaten/Kota diperlihatkan oleh tabel berikut :
Tabel 12. Sebaran Lokasi dan Luas Target GN-RHL perKabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun2007/2008
No Kabupaten/Kota Luas (ha)
1 Agam 8.6152 Limapuluh Kota 11.9553 Padang Pariaman 3.8404 Pasaman 4.6555 Sawahlunto/Sijunjung 6.3256 Solok 11.4257 Tanah Datar 7.6688 Pesisir Selatan 2.8309 Solok Selatan 2.18010 Pasaman Barat 1.45511 Dhamasraya 85012 Padang 1.81013 Bukittinggi 14014 Payakumbuh 1.05015 Pariaman 37016 Padang Panjang 15517 Sawahlunto 2.74018 Solok 972
Sumber: Diolah dari data rencana dan realisasi pembuatan tanaman GN-RHL Propinsi Sumatera Barat
REDD: Antitesis Reboisasi?
116 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel sebaran tersebut memperlihatkan target tertinggi GN-RHLadalah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Solok. Luas lahan kritisterluas di Propinsi Sumatera Barat memang terdapat di duakabupaten ini. Mungkin itu yang menyebabkan mengapa di duakabupaten ini dipasang target GN-RHL terbesar. Alasan ini jugatentu sinergis dengan posisi kedua kabupaten ini yang terletak dibagian hulu DAS besar. Berikut adalah data lahan kritis SumateraBarat.
Tabel 13. Luas Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di PropinsiSumatera Barat
Kabupaten/Kota Kawasan HutanDalam (ha) Luar (ha) Jumlah (ha)
Pasaman 8,260 7,750 16,010Agam 7,410 7,190 14,60050 Kota 11,980 24,670 36,650Tanah Datar 11,120 9,090 20,210Solok 20,090 24,720 44,810Sawahlunto/Sijunjung 7,710 33,920 41,630Padang Pariaman 2,210 12,950 15,160Padang 3,090 5,400 8,490Pesisir Selatan 5,220 11,800 17,020Jumlah 77,090 137,490 214,580
Sumber: diolah dari data Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
Target luasan hutan dan lahan terrehabilitasi ini sebenarnya tidaksignifikan untuk memulihkan luasan hutan dan lahan kritis. Karenahanya akan merehabilitasi 34,8% dari 214.580 ha hutan dan lahankritis. Artinya seluas 139.844 ha hutan lahan akan tetap kritis. Inibelum mempertimbangkan kemungkinan penambahan luasan hutan
REDD: Antitesis Reboisasi?
117Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan lahan kritis, karena laju kerusakan hutan dan lahan setiaptahunnya di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang angkanya jugarelatif tinggi.
Tingkat keberhasilan realisasi GN-RHL ternyata hanya sebesar74,9%. Tingkat realisasi tertinggi berada pada kegiatan reboisasi(GN-RHL di dalam kawasan hutan) yang mencapai 87%. Sedangkanrealisasi keberhasilan penghijauan (GN-RHL di luar kawasan hutan)hanya 61,03%. Realisasi pembuatan hutan rakyat juga hanya 61,12%.
Tabel 14. Perbandingan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahanmenurut Rencana dan Realisasinya di PropinsiSumatera Barat
Dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Hutan rakyatRencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %39.054 34.294 87% 35.682 21.777 61,03 34.612 21.157 6112%
Sumber: diolah dari data realisasi GN-RHL BP DAS Agam Kuantan
Ada dua hal yang diperlihatkan oleh tabel di atas. Yang pertamaadalah meskipun luasan lahan kritis di luar kawasan hutan lebihbesar dibandingkan dengan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan,BP DAS Agam Kuantan lebih memilih untuk mengutamakankegiatan penghutanan kembali di dalam kawasan hutan. Karenatarget reboisasi di dalam kawasan hutan mencakup setengah dariluas kawasan hutan yang kritis. Sedangkan target penghijauan diluar kawasan hutan hanya berkisar ¼ dari luas lahan kritis di luarkawasan hutan.
Tabel ini juga memperlihatkan realisasi pencapaian target lebihtinggi pada kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan, yaitumencapai 87%. Sedangkan realisasi penghijauan di luar kawasanhutan hanya 61,03%. Jika ukuran keberhasilan GN-RHL harusmencapai 75%, maka bisa disebutkan kegiatan GN-RHL di luarkawasan hutan tidak berhasil.
REDD: Antitesis Reboisasi?
118 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Jika melihat perbandingan angka tersebut, bisa disebutkan adakecenderungan BP DAS lebih mengutamakan melakukan kegiatanreboisasi di dalam kawasan hutan, ketimbang melakukanpembangunan hutan rakyat dan penghijauan lainnya di luar kawasanhutan, yang secara statistik luasnya lebih besar. Sayangnya tidakditemukan penjelasan yang bisa menerangkan mengapa hal tersebutterjadi. Juga tidak ditemukan alasan-alasan mengapa tingkat realisasireboisasi kawasan hutan lebih tinggi jika dibandingkan dengankegiatan penghijauan di luar kawasan hutan. Mungkinkah adaperbedaan keseriusan pelaksanaan antara reboisasi denganpembuatan hutan rakyat.
Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi yang sebesar 56.026ha atau 74,9% dari rencana, maka pada akhir tahun V (2007/2008),masih akan tersisa hutan dan lahan kritis seluas 158.554 ha atausebesar 73,9% dari total lahan kritis pada saat GN-RHL dimulai.Jumlah luasan ini masih sangat mungkin bertambah, mengingat padasaat yang bersamaan dengan pelaksanaan GN-RHL, tidak bisadikesampingkan kemungkinan terjadinya pengrusakan yangmengakibatkan kerusakan hutan, yang angkanya bisa jadi lebih tinggidibandingkan dengan kemampuan realisasi GN-RHL merehabilitasihutan dan lahan setiap tahunnya.
3.2.2. POTRET PELAKSANAAN GN-RHL DI NAGARIAMPALU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
1. Gambaran Umum Lokasi dan Masyarakat Nagari AmpaluNagari Ampalu terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban
Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat. NagariAmpalu merupakan salah satu tipikal masyarakat dan daerahperdesaan Minangkabau yang berada di sekitar kawasan hutan. Secarageografis letaknya adalah di wilayah timur Propinsi Sumatera Barat.Di sebelah utara dan timur daerah ini berbatasan langsung dengankawasan hutan kabupaten Kampar Propinsi Riau, sedangkan di
REDD: Antitesis Reboisasi?
119Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
bagian selatan bagian berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datardan Kabupaten Sijunjung.
Nagari Ampalu terdiri atas 6 jorong yang merupakan unitteritorial perdesaan di bawahnya, yaitu : Jorong Koto, Jorong PadangAur, Jorong Padang Mangunai, Jorong Mangunai, Jorong Guguk,dan Jorong Siaur. Menurut data Kantor Wali Nagari Ampalu (2010),jumlah penduduk nagari ini tercatat 4.218 jiwa, yang terdiri atas 2.222perempuan dan 1.996 laki-laki.
Sebagaimana daerah perdesaan Minangkabau umumnya,masyarakat Nagari Ampalu juga memiliki struktur sosial yangditandai oleh keragaan sistem sosial khas dengan susunan masyarakatyang terdiri atas kesatuan organisasi sosial dan kekerabatanberdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal system). Setiap anak yangdilahirkan dalam keluarga secara otomatis menjadi anggota darikeluarga kelompok kerabat ibunya atau keluarga matrilineal (matrilinealfamily). Setiap keluarga matrilineal adalah merupakan kelompokkeluarga luas (extended family) mulai dari kesatuan keluarga yang lebihkecil hingga yang lebih besar di atasnya, meliputi: kelompok keluargasamande, saparuik, sapayuang, dan sasuku.
Kelompok samande merupakan kesatuan keluarga matrilinealterkecil tetapi tidak sama dengan keluarga batih (nuclear family).Keluarga samande merupakan kelompok keluarga matrilineal yangbiasanya terdiri dari tiga generasi atau senenek. Kelompok yanglebih besar atau kesatuan dari beberapa keluarga samande disebutsaparuik, yang bisa terdiri dari empat sampai lima generasi. Keluarga-keluarga matrilineal inilah yang biasanya mendiami rumah gadang,rumah tradisional yang dimiliki secara komunal oleh keluarga luasterdiri dari beberapa keluarga inti yang memiliki hubungan samandeatau saparuik.
Kelompok yang lebih besar dan merupakan kesatuan daribeberapa kelompok orang yang saparuik disebut sapayuang atau biasajuga disebut sakaum. Kesatuan kelompok keluarga atau kerabat yangsapayuang atau sakaum ini biasanya merupakan kelompok keluarga
REDD: Antitesis Reboisasi?
120 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
matrilineal dari orang-orang yang “saharato pusako dan sapandampakuburan,” yakni orang-orang yang secara komunal memiliki hakatas harta pusaka dan tanah permakaman. Sedangkan kelompokkeluarga yang lebih luas atau kesatuan dari beberapa kelompokkeluarga saparuik disebut sasuku. Di antara orang-orang sekeluarga(sekerabat matrilineal) ini biasanya mengidentifikasi diri sebagaisadunsanak, atau menyebutkan keluarga awak (keluarga saya ataukeluarga kami) dan memiliki semacam perasaan bersama atausolidaritas kelompok (solidarity group) karena merasa saino samalu (satukehormatan), saharato (kepemilikan harta atau kekayaan bersama)dan sapusako (satu warisan).
Di dalam tatanan masyarakat matrilineal Minangkabau, perempuanmemiliki kedudukan sebagai pilar utama penerus garis keturunankeluarga, pewaris harta pusaka komunal serta sekaligus penjamineksistensi dan kontinuitas kebudayaan matrilineal suku bangsabersangkutan. Jika dibandingkan dengan kedudukan perempuan itu,
REDD: Antitesis Reboisasi?
121Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Adat minangkabau memiliki sejumlah kelompok suku berdasarkan ikatanmatrilineal. Kelompok suku Melayu sebagai kelompok terbesar, memilikipenguasaan terhadap tanah ulayat yang paling luas di Nagari. Sumber : Q-Bar
kedudukan laki-laki di dalam keluarga Minangkabau tentulahberbeda. Misalnya, anak laki-laki “tidak punya tempat” di rumahibunya karena rumah gadang adalah “milik anak-anak perempuan”sebagai bagian dari pusaka tinggi dan harta komunal yang diwariskanmenurut garis ibu, dari niniek turun ka gaek, dari gaek turun ka uwo,dari uwo turun ka mande, dari mande turun ka anak perempuan. Meskipundemikian di dalam struktur keluarga matrilineal Minangkabau jugadikenal adanya jabatan pemimpin yang hanya dapat diemban laki-laki seperti dinyatakan dalam pengungkapan “nan ditinggikansarantiang dan didahuluan selangkah” (yang ditinggikan seranting dandidahulukan selangkah) oleh keluarga atau kaumnya yang lazimdisebut ninik mamak.
Tradisi merantau juga merupakan bagian inhern dari identitaskesukubangsaan dan misi budaya Minangkabau yang dapat dijumpaidi Nagari Ampalu. Tradisi ini terutama terkait dengan kaum laki-lakiyang biasanya sejak muda telah dianjurkan untuk pergi merantau,seperti kata pepatah adat: ka ratau madang di hulu babuah babungo balun,ka rantau bujang dahulu di kampuang paguno balun. Artinya laki-laki dalammasyarakat Minangkabau baru dihargai sebagai orang dewasa apabilasudah pergi merantau meninggalkan kampung halaman.
Demikianlah pula di Nagari Ampalu, masyarakat nagari ini terdiriatas beberapa kelompok suku yang ditarik berdasarkan ikatanmatrilineal. Pola permukiman penduduk di daerah ini mengelompokmenurut kelompok suku dan terpencar menurut sebaran jorong yangada. Setiap bagian tanah atau lahan di daerah ini diidentifikasi sebagaikepemilikan komunal ulayat matrilinealnya. Adapun kelompok sukumatrilineal terbesar di nagari ini adalah suku Melayu. Suku Melayusekaligus merupakan kelompok suku yang memiliki tanah ulayatpaling luas di nagari ini.
Sebagian besar penduduk Nagari Ampalu menggantungkanhidupnya dari kegiatan pertanian. Usaha tani yang dijumpai di daerahini terutama adalah sawah dan kebun. Rata-rata setiap keluarga dinagari ini memiliki sawah meskipun kecil. Kegiatan berkebun yang
REDD: Antitesis Reboisasi?
122 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
lazim disebut berladang di daerah ini tampak dengan pengusahaanlahan-lahan di sekitar kampung hingga pinggir kampung. Tanamanutama perkebunan penduduk di daerah ini adalah karet. Ada jugadi antara penduduk yang mengusahakan cocok tanam palawija, tetapitidak banyak yang mengupayakannya. Di samping ada juga yangmelakukan kegiatan berternak sapi, ayam atau memelihara ikandengan membuat kolam (tebat) ikan. Ada juga penduduk yangbekerja sebagai pedagang. Untuk memenuhi kebutuhan yang harusdibeli ke pasar, penduduk harus pergi ke luar desa. Pasar terdekatdari nagari ini adalah pasar Halaban yang terletak kurang lebih 15km dari Ampalu. Di antara warga pun ada yang merantau kePekanbaru, Medan, Jakarta, atau ke daerah di Sumatera Barat lainnya.Dikarenakan rata-rata pendidikan penduduk yang relatif rendahyakni yang terbesar hanya hingga SLTP, kebanyakan perantau daridaerah ini tidak banyak yang menjadi PNS.
Nagari Ampalu sendiri sejatinya memiliki potensi sumber dayaalam yang sangat tinggi, salah satu kekayaan nagari ini adalah hutan.Luas hutan di Nagari Ampalu adalah 5.043 ha. Selain itu, jugaterdapat lahan terlantar seluas 200 ha dan kebun seluas 1586 ha.Dengan lahan yang sangat luas semestinya bisa meningkatkanekonomi masyarakat di Nagari Ampalu.
2. Pelaksanaan GN-RHL dan Permasalahannya di NagariAmpaluPada Tahun 2005, Nagari Ampalu pernah dijadikan lokasi
kegiatan program GN-RHL. Kegiatan GN-RHL ini bagian dariupaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkanfungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, danperanannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetapterjaga di Nagari Ampalu.
Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatanGN-RHL di Nagari Ampalu dilakukan dengan menunjuk salah satukelompok tani untuk melaksanakannya, yaitu Kelompok Tani
REDD: Antitesis Reboisasi?
123Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Minang Malaco. Lokasi kegiatan GN-RHL ini secara persisnyadilakukan di lahan suku Melayu yang meliputi tanah ulayat darikelompok kaum Dt. Lelo Mangkuto, Dt. Rajo Putiah, dan Dt. RajoMalano. Di dalam prakteknya meskipun dilakukan di atas lahansuku Melayu, anggota kelompok tani tidak semuanya anakkemenakan suku Melayu saja.
Sebelum kegiatan GN-RHL ini dilaksanakan di Nagari Ampalu,Dinas Kehutanan terlebih dauhulu melakukan sosialisasi denganmemberikan informasi tentang rencana kegiatan GN-RHL yang akandilakukan di nagari ini. Kemudian dilakukan survei atau pengamatanterhadap lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan GN-RHL. Lokasiyang dipilih adalah lahan-lahan kosong yang berada di KanagarianAmpalu. Lahan kosong yang akan dijadikan tempat kegiatan GN-RHL tersebut diminta persetujuan kepada pemilik lahan/tanah ulayat,agar dikemudian hari tidak akan menimbulkan masalah.
Setelah mendapatkan persetujuan dari ulayat pemilik lahan, DinasKehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengukuranterhadap lahan yang akan dijadikan lokasi kegiatan GN-RHLtersebut. Kriteria pemilihan lokasi ditentukan dari minat masyarakatterhadap kegiatan GN-RHL dengan memperhatikan wilayah daerahaliran sungai (DAS). Dalam kegiatan GN-RHL yang akan dilakukandi Nagari yang ditunjuk, masyarakat dilibatkan dari tahapperencanaan sampai pada tahap pelaksanaan karena kegiatan GN-RHL yang akan dilakukan di lokasi yang ditunjuk, berdasarkanusulan dari nagari setempat. Kegiatan GN-RHL di Nagari Ampalubarulah kemudian dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersamaantara Dinas Kehutanan dengan Kelompok Tani Minang Malacotentang kegiatan GN-RHL ini.
Dalam pelaksanaan kegiatan program GN-RHL ini, ternyataterdapat sejumlah kendala yang menjadi permasalahan mendasardihadapi, yakni :
1. Pengorganisasian kelompok tani mitra GN-RHLMeskipun program GN-RHL ini telah dirancang dengan
REDD: Antitesis Reboisasi?
124 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
mengakomodasi pendekatan partisipatif lewat pelibatanmasyarakat desa, namun pelaksanaannya sesungguhnya hanyasemu. Penetapan kelompok tani menjadi mitra dalampelaksanaan GN-RHL masih dilakukan sebatas formalitas-prosedural. Sosialisasi kepada masyarakat dan begitu pulapendampingan yang dilakukan terhadap kelompok tani mitraamatlah minim. Hal ini tampak terbukti bahwa banyak wargatermasuk dari anggota kelompok tani sendiri ternyata tetaptidak mengetahui dengan jelas kegiatan GN-RHL ini. Bakannamanya saja mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanyaada kegiatan dengan Dinas Kehutanan kabupaten. Sementaraitu pengorganisasian kegiatan yang dilakukan pada lokasilahan milik suku Melayu yang seakan-akan mengakomodirsistem budaya lokal yang mengatur tentang kepemilikan tanahsecara ulayat, hal ini jelas bertentangan dengan sistemtradisional itu sendiri. Tidaklah mungkin partisipasi sosialakan bisa diharapkan terbina manakala kesetaraan dankeadilan dari keterlibatan masyarakat diabaikan. Pola yangditerapkan dalam pelaksanaan GN-RHL di nagari Ampaluini justru membawa implikasi hubungan yang mengukuhkanadanya pembedaan kedudukan suku Melayu menjadi ibaratsebagai induk semang karena pemilik ulayat lahan, sedangkansuku lainnya adalah penggarap atau buruh tani. Demikianpula dalam hal penentuan bibit yang ditanam dalam GN-RHL, meskipun inventarisasi kebutuhan dan aspirasi darimasyarakat dilakukan, namun kemudian realisasinya tetap sajalebih dominan ditentukan oleh pihak pemerintah;
2. Pemahaman para pihak terhadap peran dan kewenangannyaPeran dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) para pihak (BPDAS, Dinas Kehutanan Propinsi, BAWASDA Propinsi,Gubernur, Bupati, TNI/Polri, Dinas Kehutanan atau dinasyang mengurusi kehutanan di tingkat Kabupaten, LSM dan
REDD: Antitesis Reboisasi?
125Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kelompok Tani) telah diatur secara jelas dalam penunjukkanpelaksanaan GN-RHL/Gerhan. Namun lemahnya sosialisasidan prakondisi pelaksanaan penyelenggaraan GN-RHLmengakibatkan beberapa pihak belum menjalankan perannyasecara maksimal;
3. Penyelenggaraan koordinasi para pihak dalam pelaksanaan GN-RHLKoordinasi antar para pihak dapat dilihat dari keterkaitandan peran serta secara aktif para pihak dalam pelaksanaankegiatan GN-RHL. Namun dalam pelaksanaannya koordinasipara pihak tidak berjalan dengan maksimal;
4. Kontribusi dan realisasi co-sharing APBD Kabupaten dalampelaksanaan GN-RHLRendahnya kontribusi APBD Kabupaten Lima Puluh Kotajuga turut mengakibatkan kegiatan GN-RHL tidak berjalandengan maksimal di daerah ini. Alokasi anggaran APBDKabupaten Lima Puluh Kota untuk seluruh kegiatan GN-RHL di kabupaten hanya 150 juta. Sementara itu pencairananggaran APBD untuk kegiatan GN-RHL di KabupatenLima Puluh Kota ini pun ternyata terlambat. Keterlambatanpencairan anggaran oleh Pemerintah Daerah ini tentu sajamengakibatkan terlambatnya kegiatan yang dilakukan.
3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Nagari AmpaluBerbicara tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di
Sumatera Barat (minus kabupaten Kepulauan Mentawai), tidakterlepas dari identitas dan entitas nagari. Pepatah lama Minangkabaumenyatakan “ulayat salingka kaum, adat salingka nagari.” Pepatahtersebut menegaskan kemustahilan untuk memisahkan keterkaitanantara ulayat sebagai objek dan nagari sebagai subjek. Ulayat bagimasyarakat Minangkabau bernilai lebih luas dari sekedar nilaiekonomis.
REDD: Antitesis Reboisasi?
126 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Menurut pembagian wilayah adat Minangkabau, Nagari Ampaluberada pada daerah Luhak Lima Puluh Kota dengan menganutbudaya keselarasan sikalek-kalek hutan. Di mana dalam sistem inipengambilan keputusan oleh tokoh adatnya, kadang menggunakancara musyawarah mufakat dan kadang bisa juga menggunakan caraotoriter sang pemimpin.
Di Nagari Ampalu terdapat 4 suku besar dari kelompok-kelompok matrilinealnya, yaitu: suku Melayu, suku Piliang, suku Bodi,dan suku Pitopang. Pada masing-masing suku ini terdapat sejumlahpemimpin kaum yang disebut ninik mamak. Jumlah keseluruhan darininik mamak di Nagari Ampalu ini adalah 57 orang ninik mamakyang bertanggung jawab atas ulayat kaum masing-masing termasukatas ulayat tanah basah maupun tanah kering.
Masyarakat Nagari Ampalu juga mengenal adanya konsep dansistem pengelolaan hutan yang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga)kategori ulayat yaitu: ulayat kaum, ulayat suku, dan ulayat nagari.Sistem pengelolaan menurut pembagian ulayat itu diatur secara jelasdi dalam adat. Batas-batas tanah atau lahan ulayat biasanyadinyatakan sesuai kesepakatan lisan yang diwariskan dari generasitua dengan menggunakan sebutan hinggo (hingga) dan berbatas tanda-tanda alam yang memakai guliang sarok kalau di bagian atas dan akasungai untuk di bagian daerah bawah.
Tentu saja keadaan ini menjadikan batas-batas dan luas kepemilikanataupun penguasaan tanah dan lahan menjadi kurang jelas atau tidakpasti. Tentang suatu kawasan hutan misalnya di sekitar hutan alamTreh Tarunjam yang terletak di wilayah ulayat Ampalu, luas dan batas-batas persisnya tidak diketahui, apalagi oleh generasi lebih muda,disebabkan luas wilayah ulayat itu menggunakan batas hinggo yangdibunyikan dalam warih balabeh adat. Oleh karenanya tidak jarang halini menjadi permasalahan tersendiri terkait adanya klaim antarmasyarakat adat. Orang dari Kampar Kiri Propinsi Riau yangberbatasan dengan Nagari Ampalu baik warga maupun ninik mamaknyamengakui itu, ulayat Ampalu umumnya mereka tidak mau melakukan
REDD: Antitesis Reboisasi?
127Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
penebangan kayu di dalam wilayah tersebut. Namun sekarang orangdari Riau pun juga ditemukan sudah mengambil kayu di wilayah ini.Pengambilan kayu di hutan ini bahkan sudah ada juga yangmenggunakan penduduk lokal sekitar Ampalu sendiri sebagaianggotanya. Inilah perbedaan antara batas ulayat dengan batasadministrasi. Hutan yang masuk dalam wilayah Riau sebenarnya hutansimpanan bagi Ampalu. Kawasan hutan yang menurut masyarakatadat tertentu dinyatakan dengan nama tersendiri dan diklaim sebagaitanah ulayat mereka, namun bisa berbeda namanya dan diklaim jugasebagai ulayat adat oleh kelompok masyarakat adat lainnya. Namabukit Tareh Tarunjam di Sumatera Barat, ternyata meliputi kawasanbukit yang dinamai Gamai-Gamai atau Bukit Cundung yang olehorang Riau disebut juga Rimbang Baling.
Di nagari Ampalu, hutan tidak hanya semata bernilai ekonomis,tetapi juga bermanfaat secara sosiologis dan sosial-budaya.Masyarakat setempat memandang hutan sebagai suatu kesatuan daripenguasaan ulayat, yang penguasaannya bersifat komunal darisusunan masyarakat yang kolektif. Dalam hal pengelolaan danpemanfaatan hutan di Nagari Ampalu, juga ditemukan aturan hukumadat yang mengaturnya.
Di dalam adat Nagari Ampalu ada tempat yang dipercayaimemiliki kesakralan oleh masyarakatnya, misalnya sebuah lokasihutan yang bernama Tareh Tarunjam. Lokasi yang terletak di bagianhutan Nagari Ampalu ini sering digunakan oleh masyarakat tempatanuntuk melakukan prosesi adat setiap tahunnya. Dalam kepercayaantradisional ini, di Tareh Tarunjam ini masyarakat secara berkala setiaptahun melakukan prosesi upacara berdoa agar dalam prosespenanaman sawah dan ladang bisa menghasilkan dan memberikemakmuran bagi penduduk. Tradisi ini sesungguhnya sudah adasejak sebelum Islam masuk ke daerah ini. Namun tradisi ini terusjuga berlanjut setelah masuknya Islam. Sebagaimana tampak di dalamprakteknya selama ini, kegiatan ini biasanya dimulai dengan terlebihdahulu disosialisasikan kepada masyarakat melalui mushala dan
REDD: Antitesis Reboisasi?
128 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
mesjid. Sayangnya kegiatan ini semakin hari semakin kurangmendapat perhatian dari warga seiring perubahan sosial yangberlangsung di perdesaan. Sejak 6 tahun terakhir tradisi yangsesungguhnya memiliki nilai kearifan lokal dalam interaksi manusiadengan lingkungannya ini dinyatakan mulai hilang di Nagari Ampalu.
Pada tahun 1987, di Nagari Ampalu pernah juga dibuatkesepakatan warga untuk menyatakan “perang” terhadap tanah-tanahyang kosong di Nagari Ampalu. Secara adat, masyarakat bersama-sama para ninik mamak menyepakati langkah-langkah untukmengolah tanah-tanah yang terlantar atau tanah kosong dalam rangkamemecahkan masalah kemiskinan yang dihadapi nagari ini. Tanah-tanah di Nagari Ampalu dahulunya dominan dikuasai oleh para elitninik mamak, kemudian mulai berubah dengan kesepakan memberiakses yang lebih besar pemanfaatannya oleh anak kemenakan.Tuntutan ini sejalan dengan upaya masyarakat setempat dalammemecahkan masalah kemiskinan. Kesepakatan adat ini bertujuanagar tanah-tanah kosong di Nagari Ampalu dapat diolah oleh anak
REDD: Antitesis Reboisasi?
129Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sebuah gedung pemerintah Kabupaten berdiri kokoh di Nagari Ampalu. Selainadanya peran pemerintah dalam pengelolaan hutan, masyarakat di negeriAmpalu juga memiliki norma dan aturan hukum adat dalam pengelolaannya.Sumber : Q-Bar
nagarinya sendiri, sehingga tidak lagi dikuasai oleh para ninik mamak.Sejak itulah penanaman tanaman tua seperti karet mengalamipeningkatan relatif pesat di Nagari Ampalu.
Patut juga dicatat bahwa lahirnya kesepakatan masyarakat Ituterjadi pada saat penggabungan kembali desa-desa yang sebelumnyadipecah. Keputusan itu ditetapkan oleh 60 orang ninik mamak yangada di Nagari Ampalu. Ninik mamak mengambil keputusan inikarena sebelumnya tanah-tanah dikuasai oleh ninik mamak secaraperorangan. Padahal tanah-tanah tersebut secara adat milikmasyarakat. Tanah-tanah yang berada 50 meter dari sawah dikuasaioleh pemilik sawah, setelah itu dibebaskan untuk dapat diolah olehanak kemenakan tergantung musyawarah bersama, tidak hanyaditentukan oleh ninik mamak saja. Bahkan menurut kesepakatan initanah-tanah kosong itu apabila tidak juga dimanfaatkan oleh kaumpemiliknya kemudian boleh saja diperjual belikan. Namun demikianjual beli tanah untuk pribadi tidak boleh dilakukan dengan orangluar nagari kecuali tetap dengan permufakatan ninik mamak dalamnagari. Ada juga ketentuan di mana jual beli tanah juga dilarangdilakukan dengan warga non muslim.
Adanya kesepakatan pemanfaatan lahan kosong ini banyak dinilaicukup membawa dampak positif, di mana sekarang tanah-tanah yangkosong kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam aturan adatdi Nagari Ampalu, ada aturan dahulunya bahwa setiap orang yangakan menikah diwajibkan untuk menanam pohon sebanyak 5 batang.Penanamannya dilakukan di dekat daerah aliran sungai. Kesepakatanini juga disertai dengan tujuan membatasi tekanan terhadap hutanalam yang ketika itu juga banyak dirambah penduduk. Sanksi adatdisepakati masyarakat di Nagari Ampalu bagi mereka yang merusaksumber daya alam hutan. Sanksi merupakan instrumen yang diyakinioleh masyarakat untuk menegakkan norma hukum adat. Sanksinyamulai dari yang ringan sampai yang berat. Sanksi yang ringan adalahdengan membayar denda, sedangkan sanksi yang terberat adalahpelanggar dihukum dengan dibuang sepanjang adat.
REDD: Antitesis Reboisasi?
130 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
3.3. PELESTARIAN FUNGSI KAWASAN HUTANMELALUI REDD? : Studi Kasus di TamanNasional Berbak Propinsi JambiOleh: Helmi, Taufiqurrohman, Husni Thamrin
3.3.1. KONDISI HUTAN DAN KEBIJAKANPENGELOLAAN HUTAN DI PROPINSI JAMBI
1. Kebijakan Eksploitatif Pengelolaan HutanBerangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan
sumber daya hutan, maka pemerintah menetapkan semua hutandikuasai oleh negara dan akan dipergunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat. Persoalannya, makna dikuasai ternyata sangatbias (dibiaskan) menjadi dimiliki dan negara direpresentasikanmenjadi pemerintah. Pemerintah prakteknya, bertindak sebagaipemilik, pengelola sekaligus pengawas. Artinya pemerintah terlibatsecara langsung dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutandan mempunyai kewenangan yang sangat luas. Menurut DjuhendiTajuddin (2002), pola pengelolaan seperti itu menimbulkan sejumlahkeberatan, antara lain: pertama, terjadi konflik kepentingan. Dalamekonomi pasar, pemerintah (sebagai representasi negara) mempunyaifungsi tujuan untuk memaksimumkan layanan. Dengan demikian,jika pemerintah juga melakukan kegiatan pengelolaan (baca:pengusahaan), maka itu akan bertumburan dengan fungsi tujuanpokoknya untuk memberikan pelayanan. Kedua, sumber daya hutansangat berlimpah. Sementara itu pemerintah tidak memiliki sumberdaya (sumber daya manusia, teknologi, dan modal) yang cukup untukdapat mendayagunakan sumber daya hutan tersebut secara optimal.Ketiga, kelembagaan yang melekat pada bentuk pengelolaan sumberdaya tersebut tidak memiliki keluwesan yang memadai untukmenangkap dan memahami kepentingan masyarakat.
REDD: Antitesis Reboisasi?
131Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Menghadapi keterbatasan dan resiko yang akan ditimbulkan, jikapemerintah mempertahankan kewenangan dan monopoli atas sumberdaya hutan, di awal Orde Baru muncul strategi baru dalampembangunan kehutanan. Pemerintah membuka akses yang luaskepada pihak swasta untuk mengelola dan memanfaatkan hutanproduksi. Pemerintahpun lantas merekonstruksi ulang kewenanganyang dimilikinya. Akhirnya pada awal kejayaan pemerintah Orde Baru,sebagian pengelolaan sumber daya hutan diserahkan kepada swasta.
Praktek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha ini populerdisebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan TanamanIndustri (HTI) atau pola lain dengan skala besar dan jangka waktu35-100 tahun dan luas yang mencapai 500 ribu hektar setiapperusahaan. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengambilkebijakan dan pemungut pajak atau retribusi atas pengelolaan danpemanfaatan sumber daya hutan tersebut. Jadilah swastamendominasi atas sumber daya hutan.
Masih menurut Djuhendi Tajuddin, bahwa kebijakan dan polapenguasaan seperti ini juga menimbulkan keberatan-keberatan yangdisebabkan beberapa faktor. Pertama, penyerahan kepada swastadianggap berlebihan. Padahal menurut FAO (1996), kemampuansetiap perusahaan untuk mengusahakan hutan secara optimaladalah mencakup kawasan seluas 150-200 ribu hektar. Kedua,karena tujuan swasta adalah mencari keuntungan maksimal, makadalam kegiatan pengusahaan hutannya kerap tidak mengindahkanasas-asas pelestarian lingkungan. Bagi perusahaan HPH,melakukan tindakan pelestarian senantiasa berkonotasi peningkatanbiaya, dan dengan demikian dianggapnya sebagai tindakanmanajemen yang tidak efisien. Ketiga, perusahaan tidak adaptifterhadap kehidupan budaya, kebiasaan, dan tata nilai masyarakatlokal.
Sementara itu masyarakat terutama yang berada di sekitar hutan,tidak mau ketinggalan. Mereka ada yang terpaksa menjadi pekerjadi perusahaan-perusahaan HPH walaupun dengan upah yang rendah,
REDD: Antitesis Reboisasi?
132 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan ada pula sebagian kecil anggota masyarakat yang melakukanpraktek pemanfaatan hutan (kayu) sendiri. Istilah populernya“bebalok1” dan membuka usaha sawmill liar yang lokasinya beradadi dalam atau pinggir hutan. Selebihnya menjadi saksi hidup ataupenonton eksploitasi kayu alam.
Kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan diatas terus berlanjut, bahkan mencapai puncaknya pada periode tahun1998 sampai dengan awal tahun 2004. Era ini dinamakan eraotonomi daerah, dimana daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah secara masal dan masif telahmengeluarkan berbagai peraturan daerah di bidang kehutanan. DiPropinsi Jambi, Perda-perda sama yakni Perda tentang IjinPemanfaatan Hutan (IPH), Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH),Ijin Usaha Hutan Tanaman (IHT), dan Perda tentang Iuran HasilHutan (IHH). Harapan bahwa kebijakan desentralisasi untukmensejahterakan masyarakat ternyata tidak tercapai, “jauh panggangdari api,” demikian dikatakan oleh Fauzi Syam,dkk (2003). Bahkan,nun jauh di pelosok Propinsi Jambi, seorang warga di kawasanpenyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera mengatakan,“katanya otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat seperti kami,tapi malah kami makin sengsara, belum ada yang berubah sampaisaat ini. Padahal sudah banyak proyek pemerintah, sudah banyakprogram Pemda di desa tapi kami tetap miskin.”
Demikianlah yang terjadi, Pemda berlomba-lomba mengeluarkanIjin Pemanfaatan Kayu, Ijin Usaha Perkebunan (dominan kelapasawit) untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD)berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Sedangkan aturan berkaitandengan kehutanan dan lingkungan seperti UU No. 41 Tahun 1999
1 Istilah yang dipakai untuk aktivitas menebang, memotong kayu bulat dari hutan alam. Hasilnya berupa kayusegi empat yang disebut dengan balok (kayu), kemudian dijual dan balok tersebut siap dijadikan bahan-bahanpertukangan seperti papan, perabot, kusen pintu, jendela dan lain-lain. Kegiatan bebalok biasanya dilakukan
secara berkelompok, di beberapa daerah Jambi untuk mengeluarkan balok dari lokasi penebangan padapembalok (Anak Ongkak) menggunakan kerbau jantan sebagai penarik.
REDD: Antitesis Reboisasi?
133Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup diabaikan. Pemda mengabaikan perannya untukmelakukan pengawasan. Partisipasi masyarakatpun sangat minimdalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan kontrol kebijakan.Akibatnya, selain proses pemberian ijin yang tidak cermat, jugaterjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan ijin.
Seperti di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, terdapat 11Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di Luar Kawasan Hutan yangkeluarkan oleh Bupati, tidak jelas lokasinya. Ijin-ijin tersebutdikeluarkan berdasarkan pada Perda tentang Ijin Pemungutan HasilHutan Kayu-Luar Kawasan Hutan (IPHHK-LKH). Dalam Perdaini yang dimaksud dengan Luar Kawasan Hutan adalah area luarkawasan hutan atau hutan rakyat. Kenyataannya setelah dilakukanpengecekan ke lapangan, ternyata pada area luar kawasan hutanyang ditunjuk dalam ijin tidak ada, bahkan sudah lama menjadikebun kelapa sawit dan padang ilalang.
Dampak yang ditimbulkan akibat sistem pengelolaan danpemanfaatan sumber daya hutan di atas adalah lebih banyak negatifnya.Kerusakan sumber daya hutan alam mencapai 1,7 juta hektar per tahunpada periode tahun 1990-an, dan pada kurun waktu tahun 1997-2000laju kerusakan meningkat menjadi 2.8 juta hektar per tahun (Holmes,2000 dalam KKI-Warsi, 2004; Santoso, 2005). Selain kerusakanekosistem hutan, juga terjadi bencana alam seperti banjir dan kebakaranhutan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah rusaknya nilai dankearifian lokal masyarakat atas sumber daya hutan dan alam, karenatidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kebijakan dan sistempengelolaan yang berorientasi pada ekonomi saja.
Tidak mengherankan kalau Mantan Menteri LingkunganIndonesia Nabiel Makarim mengatakan, bahwa hutan di Indonesiaakan habis dalam waktu 20 tahun mendatang. Jambi yang terkenaldengan hutan alamnya, kini dalam kondisi yang memprihatinkan,yang membuat para pendekar kehutanan semakin jantungan. Alhasil,sampai dengan bulan Januari 2004, di Propinsi Jambi tercatat 2 HPH
REDD: Antitesis Reboisasi?
134 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan 1 ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yangmasih aktif yakini HPH PT. Asialog (61.239 hektar), PT. Putra DutaIndah Wood (61.000 hektar) yang berada di Kabupaten Muaro Jambi,dan PT. Harapan Tiga Putra (20.000 hektar) di Kabupaten Bungo2.Sisanya hanyalah kawasan-kawasan taman nasional3 dan kawasaneks HPH (lebih kurang 588.189 hektar) yang sudah semakinterancam kepunahan.
Menghadapi kondisi hutan di atas, kalangan penggiat kehutananterutama NGO, akademisi, dan sebagian kecil pemerintah (instansikehutanan) mulai menawarkan konsep pengelolaan dan pemanfaatanhutan berbasis masyarakat. Alasannya cukup jelas, bahwa polapengelolaan yang selama ini diterapkan, terbukti hanya mengun-tungkan kalangan pengusaha dan pundi-pundi keuangan pemerintah.Selain itu, memang tidak bisa dielakkan bahwa pengelolaan hutantropis secara lestari hanya dimungkinkan dengan melibatkanmasyarakat lokal. Kiranya ini juga didasarkan pada fakta bahwasebagian besar masyarakat sekitar hutan di Indonesia, tak terkecualidi Propinsi Jambi (lebih dari 1.000 desa) hidup di bawah garis danbayang-bayang kemiskinan.
2. Kondisi Lahan Gambut di Propinsi Jambi:Pemanfaatan dan Ancaman
Upaya pemantauan hutan rawa gambut, yang merupakan prosesyang berkelanjutan diharapkan dapat mengindentifikasi perubahan-perubahan dan kecenderungan yang ada, sehingga para pengambilkeputusan dapat mengkaji apakah intervensi suatu kegiatan atauproyek dapat mencapai tujuannya, atau apakah diperlukan upayamerefokus kegiatan yang sedang berjalan.
2 Berdasarkan Data Pokok Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, sampai dengan Bulan Juni tahun 20043 Di Propinsi Jambi terdapat 4 taman nasional yakni sebagian besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman
Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit Dua Belas, dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
REDD: Antitesis Reboisasi?
135Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Tabel 15. Data sebaran, luas dan kandungan karbon lahangambut Propinsi Jambi tahun 1990 – 2002
No Kabupaten Luas (Ha) Kandungan C(Juta Ton)
1990 2002 1990 20021 Tanjung Jabung Barat 142,255 142,255 333.83 260.652 Tanjung Jabung Timur 266,304 266,304 683.19 538.973 Batanghari dan Ma. Jambi 257,506 257,506 682.07 520.124 Sarolangun 41,283 41,283 129.27 83.975 Merangin 3,525 3,525 15.78 7.016 Kerinci 3,093 3,093 3.38 0.927 Kota Jambi 2,094 2,094 3.13 1.338 Tebo dan Bungo 779,000 779,000 0.31 377.28
Jumlah 716,839 716,839 1,850.97 1,413.79
Lahan/tanah gambut di Propinsi Jambi menyebar di rawa-rawa,yaitu lahan yang menempati posisi peralihan di antara ekosistemdaratan dan ekosistem perairan. Sepanjang tahun atau dalam jangkawaktu yang panjang dalam setahun, lahan ini selalu jenuh air(waterlogged) atau tergenang air. Tanah gambut menempati cekungan,depresi, atau bagian-bagian terendah di pelembahan, danpenyebarannya terdapat di dataran rendah sampai dataran tinggi.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatankonservasi kawasan TNB di Jambi, yakni pertama, perencanaan tataruang, pengkajian dan pemantauan, dan kedua, peningkatankapasitas kelembagaan dan kepedulian lingkungan. Kegiatanpemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan terhadapkawasan Berbak secara keseluruhan (Greater Berbak), yang didalamnya banyak tercakup permasalahan yang terkait dengan hutanrawa gambut.
Kegiatan pemantauan hutan rawa gambut di kawasan Berbakdilakukan melalui beberapa pendekatan/tingkatan, antara laindengan pendekatan/tingkatan bentang alam, mengingat luasnya
REDD: Antitesis Reboisasi?
136 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kawasan tersebut. Pemantauan pada tingkatan lain seperti ekosistem/komunitas, populasi/spesies, sosial ekonomi, partisipasi masyarakat,hukum dan peraturan, dan kapasitas serta efektifitas pengelolaanjuga telah dipersiapkan dalam strategi pemantauan dan evaluasi yangada. Dalam strategi tersebut, juga telah dipilih beberapa indikator/parameter yang perlu dipantau, serta cara atau bahan (tools) untukkegiatan pemantauan dan evaluasi.
Hutan rawa gambut Berbak merupakan koridor satwa kawasankonservasi tersebut. Sistem hidrologi di kawasan TNB lebih banyakdipengaruhi oleh keberadaan hutan rawa gambut. TNB, yang jugamerupakan Situs Ramsar pertama di Indonesia, dengan luas ± 162,700ha sebagian besar terdiri dari hutan rawa gambut dengan beberapasungai yang mengalir di dalamnya, seperti Sungai Air Hitam Dalamdan Sungai Air Hitam Laut. Di samping mempengaruhi sistemhidrologi, hutan rawa gambut diyakini juga berfungsi sebagaipenyimpan karbon di alam, mengingat banyaknya kandungan organikyang tersimpan di dalam lahan dan juga hutan yang ada di atasnya.
Lahan gambut dianggap sebagai lahan bermasalah karenamempunyai sifat marginal dengan beberapa kendala apabiladikembangkan sebagai lahan pertanian. Kendalanya antara lain: (1)daya dukung bebannya (bearing capacity) rendah sehingga akartanaman sulit menopang beban tanaman secara kokoh; (2) dayahantar hidrolik secara horizontal sangat besar tetapi secara vertikalsangat kecil sehingga mobilitas dan ketersediaan air dan haratanaman rendah; (3) bersifat mengkerut tak balik (irreversible) sehinggadaya retensi air menurun dan peka terhadap erosi, yangmengakibatkan hara tanaman mudah tercuci; dan (4) terjadinyapenurunan permukaan tanah (subsidence) setelah dilakukanpengeringan atau dimanfaatkan untuk budi daya tanaman.
Pengembangan pertanian di lahan gambut harus memperhatikansifat edapologi lahan dan produksi yang dapat dicapai, fungsilingkungan dari lahan gambut perlu diperhatikan yaitu sebagai (a)penyangga daerah sekitarnya seperti reservoir air, (b) rosot karbon
REDD: Antitesis Reboisasi?
137Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan juga penghasil emisi gas rumah kaca (apabila terbakar), (c)pencegah banjir pada saat musim kemarau, penyimpan air selamamusim hujan dan melepaskannya setelah kemarau, (d) habitatberbagai flora dan fauna langka serta spesifik (cagar alam), dan (e)menyimpan keajaiban seperti adanya air hitam (water black stream).
Pemanfaatan lahan gambut untuk usaha pertanian memerlukanpengetahuan dan teknologi khusus, karena sifatnya yang khas danberbeda dengan lahan lainnya agar tidak rusak dan sangat merugikan.Kebakaran lahan gambut hampir terjadi setiap tahun. Penyebabnyaadalah kondisinya rawan kebakaran yang berkaitan dengan agrofisiklahan dan lingkungan, termasuk pranata hidrologi, aspek sosialekonomi yang terkait dengan kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah,dan norma-norma sosial yang berkembang, termasuk persepsi petanitentang lahan gambut. Dampaknya bervariasi, bergantung padaintensitas kebakaran. Kebakaran ringan hanya berakibat pada kenaikanbiaya usaha tani, sedangkan kebakaran berat menimbulkan dampakyang sangat luas seperti degradasi lahan, terjadinya lahan tidur,kerusakan pranata hidrologi, perubahan pola tanam, hilangnya matapencaharian penduduk, dan migrasi penduduk ke luar desa.
Resort Air Hitam Dalam (AHD), Wilayah ini secara umummerupakan hutan rawa gambut dan hutan dataran rendah, beradadi bagian paling barat kawasan TN Berbak. Berbatasan langsungdengan beberapa desa, antara lain, Sungai Rambut, Desa SungaiAur, dan Gedung karya. Wilayah AHD mengalami tekanan yangsangat besar akibat aktivitas penebangan liar. Hal ini sangatberpengaruh buruk bagi pengelolaan kawasan ini.
Resort Air Hitam Laut (AHL). Wilayah ini meliputi daerah dibagian tengah dari kawasan TN Berbak, yang merupakan kawasanhutan rawa gambut dan hutan bakau. Di bagian Barat, wilayah iniberbatasan dengan Desa Air Hitam Laut. Pada tahun 1997 daerahini mengalami kebakaran yang cukup banyak menghabiskan kawasanhutan yang masih bagus kondisinya. Ancaman dan gangguan lainyang teridenfikasi di daerah ini adalah penebangan liar, pengumpulan
REDD: Antitesis Reboisasi?
138 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
getah jelutung, pencarian ikan, perburuan fauna (ular phyton, biawak,ular kadut, harimau sumatera).
Resort Simpang Datuk. Wilayah ini merupakan wilayah bagianUtara TN. Berbak, berbatasan dengan Desa Simpang Datuk. Sebagiandaerah ini masih berupa hutan rawa gambut yang cukup baik, sebagianlain berupa area sisa kebakaran yang terbuka berupa semak.
Tabel 16. Ancaman dan gangguan yang teridenfikasi didaerah ini adalah penebangan liar, pengumpulangetah jelutung, pencarian ikan, perburuan fauna(ular phyton)
Wilayah Cakupan Daerah Tipe Daerah
Cemara Daerah Pantai Hutan bakau, hutanCemara dan pantai, perkebunanperbatasan kawasan kelapa persawahan.TN. Berbak –Desa Cemara.
Pesisir Jambat Daerah pantai Hutan bakau, hutandi sekitar muara pantai, perkebunansungai Jambat dan kelapa, persawahandaerah Tj. Jabung.
Resort Air S. Bungur, Batu Pahat, Hutan rawa gambut,Hitam Dalam Kayu Aro, Selabor hutan dataran
rendahResort Simpang Wilayah kerja resort Hutan rawa gambut,Datuk Simpang Datuk hutan dataran
bagian Utara rendahResort Air S. Simpang Gajah, Hutan rawa gambut,Hitam Laut S. Sp Kubu, hutan dataran
S. Sp. Melaka rendah, daerah sisakebakaran
REDD: Antitesis Reboisasi?
139Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
3.3.2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTANDI PROPINSI JAMBI
1. Aktivitas Pelestarian Fungsi Hutan dan Pengelolaan HutanBerbasis Masyarakat di Propinsi Jambi
A. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan LahanTahun 2003, Departemen Kehutanan berencana melaksanakan
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), untukmemperbaiki hutan dan lahan yang dalam kondisi kritis agar dapatberfungsi secara optimal kembali, sehingga dapat memberikanmanfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program GN-RHL dilaksanakan pada DAS yang kondisinyakritis, dengan target seluas 3 juta hektar yang akan dilaksanakandalam waktu 5 tahun. GN-RHL dimulai pada tahun 2003 pada 29DAS yang berada di 15 propinsi dan tersebar di 145 kabupaten/kota, seluas 300.000 ha. Selanjutnya pada tahun 2004 seluas 500.000ha, tahun 2005 seluas 600.000 ha, tahun 2006 seluas 700.000 ha,dan tahun 2007 seluas 900.000 ha.
Sasaran GN-RHL di 15 propinsi tersebut adalah Pulau Jawameliputi seluruh propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Sumateraberada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, danLampung. Untuk Kalimantan hanya di Kalimantan Selatan,sedangkan Sulawesi di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan SulawesiSelatan.
Seperti diketahui, kondisi hutan dan lahan Indonesia saat initelah menjadi keprihatinan nasional, laju deforestasi hutan setiaptahunnya sangat besar sehingga lebih dari 43 juta hektar hutan danlahan saat ini dalam keadaan terdegradasi. Kenyataan ini telahmengakibatkan terjadinya peningkatan bencana alam hidro-meteorologi yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Akar penyebab terjadinya bencana alam tersebut sebagian besar
REDD: Antitesis Reboisasi?
140 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
karena rusaknya lingkungan terutama di daerah hulu yang berfungsisebagai daerah resapan yang juga merupakan daerah tangkapan air(catchment area). Oleh karena itu upaya penanggulangan yangdiperlukan adalah mengembalikan kondisi daerah hulu kepadafungsinya sebagai daerah yang dapat menahan limpahan airpermukaan (run off) dan memperbaiki lingkungan fisik dengan carayang ramah lingkungan, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan.
Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan GN-RHL adalah tersedianya bibit yang berkualitas dan dalam jumlahyang cukup. Untuk tahun 2003 dibutuhkan bibit sebanyak242.805.500 batang, meliputi jenis MPTS (Multi Purpose Tree Species)sebanyak 104.649.130 batang, jenis kayu-kayuan sebanyak138.156.370 batang.
Namun demikian, GN-RHL ternyata dinilai “gagal” mengatasilaju kerusakan hutan di Indonesia, termasuk di Propinsi Jambi. Diwilayah Barat Propinsi Jambi, GN-RHL gagal menghijaukan sekitar1.850 ha hutan kritis di Kabupaten Kerinci selama 2006. Hutandan lahan kritis yang gagal direhabilitasi itu mencapai 69 persendari sekitar 2.700 ha areal hutan kritis. Hutan dan lahan kritis yangberhasil direhabilitasi di daerah itu hanya sekitar 850 ha atau 31persen.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci waktu itu, ZairusZakaria di Jambi mengatakan, kegagalan rehabilitasi hutan didaerahnya disebabkan bibit tanaman untuk rehabilitasi hutan tidakmemenuhi syarat. Sekitar 1,2 juta bibit durian, 4.000 ribu batangbibit kemiri, dan 30.000 batang bibit kemiri untuk GN-RHL didaerah itu tidak layak ditanam. Seluruh bibit tanaman itu ditolakDinas Kehutanan Kerinci.
Sementara di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi, GN-RHLjuga mengalami “kegagalan.” Salah satu penyebabnya adalah korupsi.Ternyata GN-RHL menjadi ajang untuk mendapat mendapatkankeuntungan pribadi. Kasus di Batanghari ini menjadi contohlemahnya pengawasan dan managemen pemerintah daerah dalam
REDD: Antitesis Reboisasi?
141Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pelaksanaan GN-RHL.Sementara di Kawasan Timur Propinsi Jambi yang meliputi
Propinsi Tanjunga Jabung Barat, Propinsi Tanjunga Jabung Timurdan sebagian Kabupaten Muaro Jambi, GN-RHL juga tidakmemberikan dampak positif terhadap fungsi ekosistem terutamahutan di kawasan ini. Kawasan TNB yang menjadi salah satu lokasiGN-RHL tetap menjadi lahan illegal logging.
B. Restorasi EkosistemSebagai sebuah instrumen pelestarian fungsi kawasan hutan,
Restorasi ekosistem secara resmi telah dikukuhkan oleh PemerintahIndonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 159 Tahun2004. Melalui restorasi ekosistem diharapkan terjadi peningkatanfungsi kawasan hutan dan dapat memberikan dampak positif bagikehidupan masyarakat di sekitar kawasan.
Keluarnya Permenhut di atas sebenarnya pernah disikapi olehNGO di Propinsi Jambi pada tahun 2004. Pada pertemuan tersebut,kalangan NGO sebagian besar tidak menyetujui konsep restorasidalam Permenhut tersebut. Proses tersebut terus bergulir. Terakhirbeberapa NGO di Jambi secara terbuka menyikapi aktivitas restorasiekosistem yang dilakukan oleh PT. REKI pada kawasan eks. HPHPT. Asia Log, khususnya di Propinsi Jambi.4
Beberapa hal yang mendasari sikap tersebut yakni, pertama, jikadisimak, ternyata konsep restorasi pada Permenhut ini sangatmembahayakan hutan. Walaupun cita ideal restorasi ekosistem bisadipahami sebagai upaya memperbaiki fungsi hutan. Namun jika yangdigunakan konsep dalam Permenhut ini, hal tersebut sulitdiwujudkan. Dengan bungkus cantik restorasi, dia nyaris samadengan kebijakan kehutanan lainnya. Sebab, untuk bisa melakukanrestorasi setiap orang atau badan hukum harus mendapatkan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan ditetapkan
4 PSHK-ODA, CAPPA, YLBHL, YCBM, FKD Jambi, PINSE, WALHI Jambi,
REDD: Antitesis Reboisasi?
142 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
melalui prosedur lelang. Artinya, sistem perizinan restorasi ekosistemharus tunduk pada Permenhut tentang IUPHHKA yakni PermenhutNo. 20 Tahun 2002 jo. Permenhut No. 12 Tahun 2008 tentang TataCara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan.
Kedua, kawasan hutan yang dimungkinkan di restorasi yaknikawasan hutan yang tidak produktif, kurang produktif dan masihproduktif. Yang menimbulkan persoalan adalah “restorasi padakawasan hutan yang masih produktif ”. Kekuatiran dengan dalihrestorasi, tapi tujuan utamanya hanya untuk eksploitasi kayu padakawasan hutan produksi yang masih produktif.
Ketiga, pada Permenhut pemegang izin wajib memenuhikewajiban finansial bidang kehutanan dan nonkehutanan yakni DanaReboisasi dan PSDH. Berdasarkan hal ini jelas Permenhut inibertujuan komersil.
Upaya Departemen memperbaiki sistem perizinan restorasi
REDD: Antitesis Reboisasi?
143Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Taman Nasional Kerinci Seblat di Propinsi Jambi. Sebagai sebuah tamannasional, pengelolaan hutan lestari di wilayah ini perlu dipertahankan, demigenerasi yang akan datang. Sumber : PSHK-ODA
ekosistem ternyata belum merubah “nafas” Permenhut No. 159Tahun 2009. Buktinya, Permenhut No. 61 Tahun 2008 tentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HutanRestorasi Ekositem Dalam Hutan Alam pada Hutan ProduksiMelalui Permohonan, masih melekatkan konsep perizinanIUPHHKA pada restorasi ekosistem.
Walaupun Permenhut No. 61 Tahun 2008 diberi judul“Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada HutanProduksi melalui Permohonan”, namun tata cara perizinan dansistem pengelolaan kawasan restorasi tidak berdiri sendiri.Permenhut ini belum memberikan solusi persoalan sistem perizinanrestorasi ekosistem yang mandiri.
Persoalan-persoalan di atas, dikuatirkan menimbulkan persoalandi masa yang akan datang. Pertama, karena sistem perizinan danpengelolaan restorasi harus tunduk pada “rezim IUPHHKA”, sangatterbuka kemungkinan bagi semua pihak untuk melakukan eksploitasisumber daya hutan, khususnya kayu melalui restorasi ekosistem.Kedua, Jika pemegang izin melakukan eksploitasi pada kawasan yangtelah direstorasi, Pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa aktivitaseksploitasi tersebut melanggar hukum, karena melaksanakan izinsesuai dengan IUPHHKA yang dimilikinya.
Diperlukan tindakan antisipasi untuk mengatasi munculnyakedua hal di atas. Pertama, mendorong sistem perizinan yangrestorasi ekosistem tersendiri merupakan langkah tepat. Sehingga“nafas” restorasi ekosistem” dapat dilaksanakan sesuai denganharapan yakni keterpaduan antara keberlanjutan fungsi ekologi,keadilan sosial dan ekonomi. Kedua, mendorong penguatan kebijakantingkat lokal (Desa dan Kabupaten) dalam rangka menjaga kawasanrestorasi ekosistem dari tindak eksploitasi pihak lain. Kebijakantersebut adalah peraturan daerah kabupaten dan kerja sama antardesa-desa sekitar kawasan dalam bentuk keputusan bersama tentangkerja sama antara desa di kawasan restorasi ekosistem.
REDD: Antitesis Reboisasi?
144 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di JambiPentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari,
sudah terlalu sering disuarakan dan dibahas dalam berbagaipertemuan. Mulai dari diskusi kecil-kecilan sampai workshop danseminar-seminar di hotel mewah. Sudah jamak dikupas, diadvokasimelalui media massa. Begitu panjang dan rumitnya perjalanan yangtelah ditempuh.
Di Propinsi Jambi, terdapat berbagai macam bentuk pengelolaanhutan berbasiskan masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut yakni hutanadat (1.218 ha) dan hutan lindung (1.037 ha) yang terdapat di DesaBatu Kerbau, Hutan Adat Desa Guguk (800 ha), Rimbo Adat DesaBaru Pelepat (780 ha), Hutan Desa Mangun Jayo (5.385 ha). Bentukhutan berbasis masyarakat ini merupakan hasil kerja sama antaramasyarakat dengan NGO di Jambi. Selain itu, terdapat bentukpengelolaan hutan dengan pola kemitraan antara perusahaan denganmasyarakat setempat yang dikembangkan oleh PT. Wira Karya Sakti(WKS)5, yaitu pola Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) seluas3.114 ha dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) seluas 12.065ha.
Kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat,keduanya di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan Desa Gugukdi Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, berada di sekitardaerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat.
Hutan Adat Desa Batu Kerbau telah dilegalisasi dengan SuratKeputusan (SK) Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentangPengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan PelepatKabupaten Bungo, meliputi 5 lokasi yakni:a. Hutan Lindung Batu Kerbau, seluas + 776 hab. Hutan Lindung Belukar Panjang seluas + 361 hac. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas + 380 ha
5 Salah satu perusahaan hutan tanaman industri yang memasok bahan baku kayu (akasia) bagi industri buburkertar PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPI). Kedua perusahaan ini merupakan unit usaha dari PT. Sinar
Mas Group.
REDD: Antitesis Reboisasi?
145Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
d. Hutan Adat Belukar Panjang, seluas + 472 hae. Hutan Adat Lubuk Tebat, seluas + 360 ha
SK pengukuhan ini memperkuat kepercayaan dan keyakinanmasyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan adat dariancaman pihak luar. Masyarakat menyadari bahwa kawasan yang diSK-kan tersebut adalah benteng terakhir bagi masyarakat dalammenyelamatkan hutan berdasarkan nilai-nilai, penguatan lembagapengelola serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga cita-cita untuk mewariskan hutan kepada anak cucu dapat terealisasi(Tim Fasilitator KKI-Warsi Jambi, 2002).
Kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau ini tidak terletak dalamsatu hamparan, akan tetapi berada pada sekeliling wilayah desa.Sementara di antara lokasi tersebut terdapat pemukiman pendudukdan kawasan hutan eks HPH.
Masyarakat membagi Hutan Adat Desa Batu Kerbau menjadiatas 2 fungsi yakni, pertama fungsi lindung di mana semua sumberdaya yang terdapat di dalamnya dipersiapkan untuk kepentingananak-cucu dan kepentingan ekologis. Hasil hutan yang bolehdimanfaatkan adalah non kayu, seperti buah-buahan, madu dengancara tidak menebang pohonnya. Kedua, fungsi adat, di mana hasilhutan kayu dan bukan kayu pada kawasan ini dapat dimanfaatkanuntuk keperluan sehari-hari masyarakat dan kepentingan umum didesa, serta tidak boleh dibawa ke luar desa atau dijual.
Sama dengan Batu Kerbau, Hutan Adat Desa Guguk seluas +800 hektar juga telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan BupatiMerangin Nomor 287 tahun 2003 tentang Pengukuhan KawasanBukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum AdatDesa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.Fungsi hutan adat juga sama dengan hutan adat Desa Batu Kerbauyakni berfungsi lindung dan berfungsi adat. untuk kepentinganmasyarakat sehari-hari. Hutan adat Desa Guguk terletak padakawasan hutan produksi tetap dan termasuk dalam areal HPH PT.
REDD: Antitesis Reboisasi?
146 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Injapsin. Awalnya terjadi konflik kawasan antara perusahaan denganmasyarakat adat Desa Guguk.
Masyarakat Desa Guguk kompak menjaga dan memelihara hutanadatnya, menghalangi dari ancaman penebangan liar, member-dayakan Hutan Adat sebagai tempat wisata di mana setiap orangyang ingin berkunjung ke sana difasilitasi alat transportasipenyeberangan berupa perahu dan pondokan di puncak Bukit“Tapanggang”. Masyarakat menjadikan Bukit Tapanggang sebagaihutan adat kebanggaan. Pemerintah Merangin memasukkan programdana reboisasi berupa bantuan 3000 bibit untuk lebih menghijaukanlagi Hutan Adat kebanggaan masyarakat Guguk dan pemerintah.
Lain yang terjadi di Batu Kerbau dan Desa Guguk, Rimbo Adatdi Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, padasaat tulisan ini dibuat masih berusaha untuk mendapatkanpengukuhan dari Pemerintah. Namun kawasan Rimbo Adat seluas+ 780 ha telah disepakati bentuk pengelolaan dan pemanfaatandalam Peraturan Desa (Perdes) Baru Pelepat Nomor 2 Tahun 2004tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rimbo Adat Datuk RangkayoMulio6. Dalam Perdes ini, Rimbo Adat berfungsi lindung dan fungsiadat seperti di Desa Batu Kerbau dan Guguk. Mengenai statuskawasan, Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio terletak pada ArealPenggunaan Lain dan kawasan eks HPH.
Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan kayu dari Rimbo Adat,diharuskan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola Hutan Adat dandisetujui oleh Kepala Desa. Sebelumnya harus memenuhi persyaratanyakni mengajukan permohonan, menyediakan bibit 5 batang bibitsebagai pengganti pohon yang ditebang, dan membayar sejumlah uangsebagai sumbangan untuk kas desa dan kelompok pengelola.
6 Datuk Rangkayo Mulio adalah nenek moyang masyarakat setempat yang merupakan keturunan dari MinangKabau. Pemberian nama Rimbo Larang dan Rimbo Rakyat Datuk Rangkyo Mulio menurut penulis, tidaklahsekedar wujud penghormatan terhadap leluhur atau hendak dikeramatkan. Namun merupakan pesan bahwa
sumber daya hutan yang ada sekarang ini merupakan bukti jerih payah para leluhur dalam menjaga danmempertahankannya. Jika tidak dijaga dan dipertahankan, kemungkinan besar generasi sekarang tidak akan lagi
menikmati manfaatnya.
REDD: Antitesis Reboisasi?
147Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Hutan Desa Mangun Jayo dibentuk atas kerja sama antaraFakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), PemerintahKabupaten Tebo, LSM Cakrawala Jambi dengan masyarakat DesaMangun Jayo. Kawasan seluas + 19.000 ha terdiri atas kawasantanah negara, hutan penelitian UGM dan Tanah Kebun Masyarakat.
Kawasan hutan desa yang sebagian besar lahan kritis, sebenarnyasudah tidak layak lagi dikatakan sebagai hutan. PemerintahKabupaten dan masyarakat Desa Mangun Jayo sepakat menjadikanHutan Desa seluas 5.385 ha sebagai sumber pendapatan desa danmasyarakat dari seluas 19.000 ha kawasan hutan. Masyarakatdiberikan kesempatan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutanyang ada di desa sebagai sumber perekonomian baru, dengan catatantidak menghilangkan fungsi hutan. Kawasan lahan kritis akibataktivitas illegal logging, karet kehutanan dan tanaman karet. (TabloidHutan Desa, Edisi Maret 2005).
Komitmen pemerintah dan masyarakat mempertahankan hutanyang tersisa di Desa Mangun Jayo, dibuktikan dengan adanya Perdestentang Pengelolaan Hutan Desa Mangun Jayo. Walaupun prosespembentukan Perdes agak tergesa-gesa, pelaksanaannya olehKelompok Pengelola Hutan Desa Mangun Jayo (KPHD-MJ) yangdipercaya sebagai lembaga pengelola, ternyata efektif.
PT. WKS mengembangkan “Hutan Tanaman Pola Kemitraan(HTPK) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) bekerjasamadengan masyarakat sekitar areal konsesi”. HTPK dikembangkandalam rangka resolusi konflik atas perambahan di areal konsesi olehmasyarakat di sekitar hutan. Berbeda dengan HTPK yangdikembangkan di areal konsesi perusahaan, HRPK dilaksanakan diluar areal konsesi.
Kedua model kemitraan (HTPK dan HRPK) ini bermaksudmengembangkan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakatdalam rangka penyediaan bahan baku akasia untuk industri bubukkertas PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPI) di Desa TebingTinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
REDD: Antitesis Reboisasi?
148 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Lahan masyarakat di luar kawasan hutan tersedia cukup luas danpemanfaatannya belum optimal. Masyarakat pemilik lahan dirangsangmembangun hutan tanaman, selain akan meningkatkan pasokan bahanbaku kayu bagi industri juga untuk meningkatkan pendapatanmasyarakat. Perusahaan membangun kemitraan dengan masyarakatpemilik lahan dalam bentuk bimbingan teknis, bantuan modal,jaminan kesempatan kerja, dan jaminan pemasaran produksi kayunya.
Program HTPK maupun HRPK telah dirintis sejak PT. WKSberoperasi dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, dan pada tahun1997 penanaman baru dapat dimulai. Pada tahun 2004 areal HTPKseluas 3.114 ha yang dikelola oleh 23 kelompok dengan anggotasebanyak 2.094 orang, sudah siap panen seluas 104 ha dan menghasilkanBahan Baku Sepih (BBS) sebanyak 12.077 ton. Sementara itu, arealHRPK seluas 12.065 ha yang dikelola oleh 78 kelompok dengan anggota7.554 orang, telah dipanen seluas 2.870 ha dengan produksi BBS
REDD: Antitesis Reboisasi?
149Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Potret Taman Nasional Berbak di Propinsi Jambi. Aktivitas REDD pada kawasanhutan rawa gambut ini berlaku Permenhut No. 30 Tahun 2009. Sumber : PSHK-ODA
sebanyak 395.697 ton (Witono dan Nuryadi, 2005).Kebijakan Pemerintah Daerah di Propinsi Jambi tentang CBFM,
sampai saat ini masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat.Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat atau hutan desa yangmenjadi fokus tulisan ini, tidak mempunyai landasan yuridis yangkuat dari Pemerintah Daerah. Perda yang diharapkan menjadiinstrumen hukum tidak ada yang memberikan peluang untukpengelolaan hutan berbasis masyarakat. Mengapa hal ini terjadi?Salah satu penyebabnya, pemerintah pusat tidak memberikankewenangan secara tegas kepada daerah untuk mengatur CBFMmelalui kewenangan otonomi. Ditambah lagi pemahaman tentangpengelolaan hutan berbasis masyarakat di daerah juga belum jelas.
Menelusuri jejak kebijakan tentang hutan adat dan hutan desa diera otonomi tidaklah susah, karena tidak banyak aturan yangmengaturnya. Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,mengatur tentang masyarakat hukum adat sebagai berikut:(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya berhak:a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yangbersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukumadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Ketentuan di atas, di satu sisi membuka kemungkinan bagi
masyarakat hukum adat melakukan pemungutan hasil hutan. Namun
REDD: Antitesis Reboisasi?
150 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
di sisi lain beberapa rumusan dalam ketentuan tersebut ternyatabelum memberikan rasa keadilan dan ketidakjelasan mengenaipemungutan hasil hutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasilhutan lengkap dengan alas haknya seperti HPH.
Pemungutan hasil hutan terutama hasil hutan kayu tidak untukdiperdagangkan, namun hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti pembangunan tempat ibadah, balai desa atau sekolah.Kebutuhan pribadi berkaitan dengan kayu adalah pembangunanrumah, pembuatan alat transportasi seperti perahu.
Ketidakjelasan dan ketidakadilan lain adalah prasyarat yang cukupberat untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adatsebagaimana dalam penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan yakni,“Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurutkenyataannya memenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;b. masyarakatnya masih dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat
yang masih ditaati; dane. masih melakukan pemungutan hasil hutan, di wilayah hutan
sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.Prasyarat tersebut dinilai cukup berat, karena untuk mengetahui
keberadaan masyarakat hukum adat tidak sekedar dilakukanidentifikasi, namun dibutuhkan kajian mendalam dan penguatankembali perangkat kelembagaan adat. Mengingat lebih dari 40 tahuntelah mengalami pemudaran peran dalam pelaksanaan pemerintahandan pembangunan di masyarakat.
Kondisi ini semakin memperihatinkan ketika penjabaran danpengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) Pasal 67 UU Kehutananini harus dengan Peraturan Pemerintah7. Saat tulisan ini dibuat, PPtersebut masih terbatas pada Rancangan Peraturan Pemerintah
7 Salah satu bentuk produk hukum yang kewenangan untuk membentuk berada ditangan Presiden.
REDD: Antitesis Reboisasi?
151Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
(RPP). Terakhir rancangan yang bertajuk “Rancangan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor...tahun 2002 tentang HutanAdat dan Masyarakat Hukum Adat”. Beberapa pasal dalamrancangan ini juga masih menimbulkan pertanyaan, seperti cakupanmasyarakat hukum adat yang akan dikukuhkan dengan PeraturanDaerah Propinsi atas usulan masyarakat atau Bupati. Jika masyarakathukum adat yang dimaksudkan mencakup satu wilayah kabupaten,tentu mustahil dilakukan mengingat perkembangan dan perubahanyang terjadi. Berbeda, jika pengukuhan tersebut dapat dilakukanterhadap beberapa atau satu komunitas yang sekarang secaraadministratif dinamakan desa, tentu akan lebih dilakukan.
Jika kebijakan tentang hutan adat dihadapkan pada ketidak-pastian, nasib yang sama juga dialami oleh hutan desa. Alinea ketigapenjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan“Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untukkesejahteraan desa disebut hutan desa”. Tidak ada penjabaran lebihlanjut mengenai hutan desa.
Sementara, hutan kemasyarakatan dijelaskan, bahwa hutan negarayang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakanmasyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Penjabaran tentang hutankemasyaratan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan(Kepmenhut) Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang PenyelenggaraanHutan Kemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehutanan yang batangtubuhnya terdiri dari 9 bab dan 59 pasal ini, memberikan ruangbagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutannya untukkesejahteraan. Kepmenhut ini, juga memberikan kewenangan bagidaerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang ijin pemanfaatanhutan kemasyarakatan.
Bagaimana sikap daerah menghadapi kebijakan pemerintah pusattentang pola-pola CFBM di atas? Bagi Pemerintah Daerah, keluarnyaSK 31 Tahun 2001 menambah dasar yuridis untuk melakukanpembebasan atau peralihan status kawasan hutan menjadi bukankawasan hutan “Areal Penggunaan Lain (APL)”. Terbukti tahun
REDD: Antitesis Reboisasi?
152 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
2001-2002 menjadi puncak kejayaan pemanfaatan dan pemungutanhasil hutan kayu melalui ijin-ijin skala kecil (50-100 ha) yakni IjinPemanfaatan Hasil Hutan (IPH) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan(IPHH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Syaratutamanya pemilik modal “Cukong” harus membentuk koperasiatau kelompok tani masyarakat sekitar hutan, kemudian digunakanuntuk mengajukan permohonan IPH atau IPHH. Dampaknya selainkerusakan hutan semakin parah, makna hutan kemasyarakatan jugaterjadi pergeseran.
Mengenai hutan adat dan hutan desa, seperti diketahui di PropinsiJambi ada yang telah dikukuhkan melalui SK Bupati seperti di DesaBatu Kerbau dan Desa Guguk, namun hal ini belum menjaminkawasan tersebut bebas dari ancaman kerusakan. Beberapa faktoryang menjadi penyebabnya adalah:
Pertama, pengukuhan hutan adat atau hutan melalui SK Bupati,tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Sementara,kebutuhan adanya pengukuhan hutan adat dan hutan desa semakinmendesak. Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari terobosanhukum melalui SK Bupati yang berlindung di bawah “payungkewenangan otonomi daerah”.
Secara substansi, pengukuhan melalui SK Bupati tidak bolehdilakukan, karena berdasarkan asas hukum “bahwa undang-undangkhusus mengenyampingkan undang-undang yang umum”. Dalamhal ini SK Bupati didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah) yang merupakan UU yang bersifatumum, sedangkan substansi yang diatur tentang hutan, maka UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mestinya dipakaisebagai UU yang bersifat khusus.
Kedua, kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah dalammendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat ataupun hutandesa. Hal ini tampak pada saat proses pembentukan, yang lebihbanyak didominasi oleh kalangan NGO berdasarkan hasil-hasil
REDD: Antitesis Reboisasi?
153Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
pertemuan dengan masyarakat sekitar hutan. Memang tidak salahjika pada proses pembentukan pemerintah daerah kurang terlibat.Namun, sebagai pihak yang mempunyai kekuatan dan kewenanganhendaknya dapat berperan secara aktif mendukung keberlanjutanCBFM yang benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Ketiga, model pemanfaatan dan pengelolaan masih terbatas padaaspek konservasi. Padahal harus diakui kebutuhan dan ketergan-tungan masyarakat terhadap hasil hutan tidak hanya bersifat jasalingkungan, namun juga manfaat non jasa, seperti kayu atau bukankayu. Sesungguhnya dibutuhkan keseimbangan manfaat antaraekonomi langsung dan konservasi melalui pelestarian.
3.3.3. REDD
Dalam perdebatan mengenai perubahan iklim, deforestasi dandegradasi hutan dipercaya menyumbang sekitar 20 % dari total emisikarbon ke atmosfir yang menyebabkan pemanasan global. Sementaradi sisi lain hutan dipercaya dapat memainkan peranan penting dalammitigasi perubahan iklim. Indonesia merupakan negara emiterkarbon terbesar ketiga di dunia yang disebabkan oleh hilangnyahutan akibat perubahan tata guna lahan, kebakaran dan penebanganyang tidak terkontrol, dan sebagainya.
Setidaknya ada beberapa masalah dalam skema REDD, pertamaberlangsungnya program REDD di Indonesia akan memunculkan“broker” karbon di tengah-tengah pemerintah daerah pemilik hutanapalagi dengan adanya otonomi daerah yang mana hak pemerintahdaerah untuk mengelola hutan. Bahkan “broker” karbon sudahmenembus taraf gubernur terkait proses REDD. Selain itu belumadanya mekanisme dan proses sertifikasi yang jelas akan menjadicelah yang bisa dimanfaatkan para broker tersebut untukmendapatkan keuntungan.
Kedua, kekhawatiran bahwa dana isentif REDD akan menjadiobjek “baru” korupsi di Indonesia sangat beralasan berkaitan dengan
REDD: Antitesis Reboisasi?
154 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
belum adanya mekanisme yang jelas dan mengingat buruknya sistemkeuangan Negara serta birokrasi di Indonesia. Pemerintah danpemerintah daerah menganggap REDD merupakan sumberpenerimaan kas negara dan daerah.
Ketiga, mengutip apa yang dikatakan M. Riza Damanik,mekanisme REDD ini menawarkan kepada negara-negara yangmemiliki hutan untuk menjaga dan mengunci hutannya denganimbalan uang. Resiko yang akan muncul dana-dana REDD ini akandipakai oleh negara untuk melengkapi lembaga perlindungan hutandengan sejumlah mobil jeep, walky talky, persenjataan, helikopterdan GPS dengan pendekatan “senjata dan penjaga” dengan cara inimengukuhkan kontrol negara dan swasta atas hutan. Mencermatitawaran ini tentunya sangat banyak yang dirugikan karena akanmembatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan,belum lagi mayarakat yang tinggal di sekitar hutan dan peng-hidupannya mengandalkan dari hasil hutan, bila akses terhadap hutanmereka dibatasi, tentu saja akan kehilangan sumber ekonomi.
Keempat, proposal REDD justru membuka kesempatan kepadapengusaha kehutanan untuk turut mendapat insentif dari mekanismeyang ditawarkan yakni berlandas kepada kekuatan legal formal yangdimiliki atas suatu konsesi kawasan hutan tertentu (seperti HPH,HTI dan perkebunan) melalui itikad pengurangan atau penghentianpemanfaatan kawasan konsesi hutan yang dimiliki oleh setiappengusaha. Dengan begini, bukan masyarakat di sekitar hutan yangmendapat keuntungan dari REDD, tapi justru mereka parapengusaha yang mendapatkan keistimewaan dari REDD dalam halfinansial, dan sekaligus terbebas dari tanggung-jawab mutlakterhadap kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukansebelumnya.
Pada bulan Desember 2009, konvensi kerangka kerja PBB untukperubahan iklim “United Nation Framework Convention on ClimateChange” (UNFCCC) akan mengadakan Conference of Party yang ke15 di Copenhagen, Denmark. Pertemuan ini akan menentukan
REDD: Antitesis Reboisasi?
155Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kesepakatan global dalam penanganan perubahan iklim yang akanefektif setelah 2012 (pasca Protokol Kyoto).
Kemudian pada konferensi di Copenhagen, delegasi RI telahmemutuskan empat hal. Pertama, Indonesia menandatanganiCopenhagen Accord demi meraih pendanaan dari negara industri.Kedua, 16 paragraf pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyonotidak menyentuh substansi dimensi kelautan dan ancaman perubahaniklim terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. Ketiga, Indonesiainkonsisten ketika berkomitmen menurunkan emisi 26 persen, tetapitidak bersedia berkomitmen menghentikan konversi hutan alam.Keempat, delegasi menggunakan ajang konferensi untukmendapatkan utang-utang baru. Uni Eropa dan Amerika Serikatberkomitmen salurkan 10 miliar dollar AS pada 2010-2012, 50persennya dalam skema utang luar negeri.
Sebagaimana diketahui, Indonesia sebelumnya telah melakukanberbagai langkah menuju REDD. Persiapan tersebut mulai dari pusatsampai ke daerah. Namun, seperti yang telah disampaikansebelumnya, bahwa persiapan tersebut ternyata belum bisamemberikan “kepastian” bagi terlaksananya REDD di Indonesia.
Di tingkat nasional terdapat Peraturan Menteri Kehutanan RINo. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi DariDeforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), dan Permenhut No. 36Tahun 2009 tentang Tata Cara Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan HutanLindung. Kedua peraturan ini khusus dipersiapkan dalam rangkapelaksanaan REDD di Indonesia.
Permenhut No. 36 Tahun 2009, ruang lingkupnya adalah kawasanhutan produksi dan hutan lindung yang dibenai izin pemanfaatanhutan. Sementara Permenhut No.30 Tahun 2009, selain HutanProduksi, Lindung, juga pada kawasan konservasi. Jadi, untukaktivitas REDD pada kawasan hutan rawa gambut Taman NasionalBerbak berlaku Permenhut No. 30 Tahun 2009.
Pada Permenhut 30 ini, Menteri Kehutanan menjadi “pemegang
REDD: Antitesis Reboisasi?
156 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
kekuasaan” pemberian Izin REDD, termasuk pada TNB. Sementarayang dapat mengajukan REDD pada TNB dan kawasan tamannasional lainnya adalah Kepala Balai Taman Nasional yang“notabene” merupakan pemerintah pusat. Artinya, berdasarkanPermenhut ini, untuk TNB dan taman nasional lain hanya bisadiajukan dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Sesuai dengan Pasal 7 Permenhut No. 30 Tahun 2009, persyaratanREDD pada hutan koservasi adalah, (a) Memiliki salinan SuratKeputusan Menteri tentang Penunjukan/Penetapan HutanKonservasi, (2) Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD,(3) Memiliki rencana REDD. Dalam kaitannya dengan TNB,tentunya tidak ada persoalan bagi Balai TNB untuk melengkapipersyaratan tersebut.
Namun, yang perlu dipertanyakan masalah akan muncul ketikapemenuhan kriteria sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai denganlampiran (2) huruf A Permenhut di atas, bahwa harus terdapat datatentang ketergantungan masyarakat terhadap lokasi ada/tidaknyakonflik; keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, dankejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan. Pertama,ketergantungan masyarakat di desa-desa sekitar kawasan terhadapTNB sangat tinggi yakni zona penyangga TNB menjadi sumberekonomi bagi masyarakat. Kedua, walaupun secara yuridismasyarakat mengetahui bahwa TNB terutama zona inti tidak boleh“diganggu gugat”, namun kenyataannya di lapangan, masyarakatsekitar kawasan masih cenderung untuk memasuki dan memanfaat-kan potensi kawasan ini. Ketiga, mengenai ketegasan dimensipengentasan kemiskinan, tentu saja tidak bisa hanya semata-matadijadikan sebagai upaya untuk melepaskan ketergantunganmasyarakat atas kawasan TNB.
Persoalan lain yang cukup mendasar adalah, hubungan antaraBalai TNB dengan Pemerintah Propinsi Jambi, PemerintahKabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Dalam konteks pengajuan rencana REDD, sesuai dengan Permenhut
REDD: Antitesis Reboisasi?
157Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
dan tata laksana kewenangan urusan pemerintahan, maka pemerintahdaerah tidak memiliki kewenangan atas TNB. Mengacu pada sistemkewenangan dalam perundang-undangan, keterlibatan pemerintahdaerah terkait tidak dalam substansi pelaksanaan REDD.
Belum adanya instrumen hukum yang memadai mengenaihubungan antar pihak-pihak berkepentingan dalam rangkamenghadapi REDD di TNB, justru akan memperbesar kekhawatiranmunculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebutsetidaknya antara Balai TNB, Pemerintah Daerah, dan masyarakatdesa yang berada di sekitar TNB.
Balai TNB saat ini telah mengajukan kawasan hutan rawa gambutTNB untuk menjadi salah satu lokasi proyek percontohan REDDdi Indonesia. Sementara pemerintah Propinsi Jambi melalui DinasKehutanan Propinsi, tampaknya juga menjadikan TNB sebagai“lahan” REDD. Demikian juga beberapa NGO di Jambi telahmelakukan kegiatan-kegiatan mempersiapkan REDD di KawasanTNB.
Aktivitas NGO tersebut diantaranya, Yayasan Gita Buana,“Membangun inisiatif peran serta masyarakat sekitar TNB dalammenyikapi isu perubahan iklim dan pengembangan program REDD(pertukaran karbon)”. Kegiatan YGB ini dilaksanakan sejak tahun2009, berakhir tahun 2011. Warsi bersama YGB dan PKBI jugamelakukan kegiatan terkait persiapan REDD di kawasan TNB yakni,“Mendorong konsultasi publik terkait REDD di komunitas”.
Sementara beberapa kegiatan YGB sebelumnya pada kawasanTNB yakni:1. Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan Lahan
Basah di sekitar TNB (2005-2006);2. Mengurangi dampak negatif dari pemulihan produktifitas
penggunaan lahan basah oleh masyarakat di sekitar penyanggaTNB (2007 – 2009);
3. Penguatan institusi pemerintahan desa di Air Hitam Laut (2009);
REDD: Antitesis Reboisasi?
158 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sedangkan NGO Pinang Sebatang (PINSE), telah melakukanberbagai kegiatan di kawasan TNB, yakni:1. Membangun alternatif keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan TNB, dengan menitikberatkan pada Pelestarian TNBsebagai Kawasan Ramsar dengan Usaha-Usaha PeningkatanTaraf Hidup Masyarakat melalui Konvensasi Rehabilitasi Lahan.
2. Pola umum program pengelolaan TNB oleh LSM PINSE;3. Climate Change, Forests, and Peatlands (CCFPI);4. Combining Community’s Income Generating Activities with Conservtion
Towards the Reduction and Prevention of Future Fire Risks in BerbakNational Park and it’s Surrounding;
5. Water for Food and Ecosystems Programme project on: Promoting theRiver Basin and Ecosystem Approach for Sustainable Management ofSouth East Asian Lowland Peatswamp Forest ;
6. Forest Fire Prevention Management Project 2 JICA Monitoring JalurHijau Terpadu;
7. Forest Fire Prevention Management Project 2 JICA Pembangunan PlotPupuk Bokasi;
8. Wetlands Poverty Reduction Project (WPRP);9. PEATLAND SOILS AND HYDROLOGY RESEARCH.
Beberapa aktivitas di TNB juga dilakukan oleh FLEGT-SP Jambiyakni membangun Pusat Informasi Kehutanan (Dinas Kehutanan),Pengamanan Hutan (Dinas Kehutanan dan Balai TNB), PenyuluhanKehutanan (Balai TNB), Pembentukan Satgas Pemberantasan IllegalLogging (JKPKH).
Mengacu pada beberapa kegiatan yang pernah dan sedangdilakukan NGO di TNB, dan pada dasarnya semua aktivitas tersebutdalam rangka pelestarian fungsi TNB dan peningkatan kapasitasmasyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan TNB.
Namun demikian, jika kembali pada kebijakan dalam rangkamenghadapi REDD, masih banyak persoalan terutama pada,pertama, hubungan antara pemerintah daerah dengan Balai Taman
REDD: Antitesis Reboisasi?
159Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Nasional serta masyarakat. Kedua, bentuk keterlibatan masyarakatdalam REDD di TNB. Ketiga, kapasitas Balai sendiri.
REDD bukan sekedar masalah pengalokasian dana miliaranrupiah, terdapat kewajiban-kewajiban ketat yang harus dilakukanoleh pemegang izin terhadap kawasan yang bersangkutan. Olehkarena itu, dari sisi kebijakan diperlukan integrasi antara Balai TNB,Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan. Bahkanintegrasi juga diperlukan dengan program-program NGO yangsedang dan akan dilakukan.
Selama ini, berbagai aktivitas (tidak saja di TNB), masihberlangsung sendiri-sendiri, bahkan terkesan masing-masing(terutama Pemerintah dan NGO) tidak “terhubung” satu sama lain.Pemerintah/Balai beraktivitas dalam rangka melaksanakan kebijakanyang telah dibuat untuk melindungi TNB, sementara NGOmelakukan penguatan pada masyarakat dalam rangka mendapatmanfaat atas keberadaan TNB.
Pemerintah Daerah, merasa tidak memiliki kewenangan atas TNBkarena menjadi urusan pemerintah pusat dan mengganggap TNBhanya beban bagi keuangan daerah. Pemerintah daerah, terutamaPropinsi Jambi tampaknya masih meragukan konsep REDD, karena:pertama, salah satu strategi pembangunan di Propinsi Jambi,menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang adauntuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatmelaui pengembangan ekonomi kerakyatan. Merupakan sebuahdilema karena REDD akan membatasi akses masyarakat atas sumberdaya hutan, bahkan pada taman nasional sama sekali tidak bolehdimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Sementara hampir 70%masyarakat Propinsi Jambi bermukim di dalam dan sekitar hutan.Untuk TNB, hal tersebut telah disajikan pada bagian sebelumnya.Kedua, tidak adanya data akurat tentang potensi hutan danperubahan penutupan kawasan yang dimiliki oleh PemerintahPropinsi Jambi sehingga deteksi cadangan karbon sulit dilakukan.Ketiga, REDD lebih mengutamakan kepentingan konservasi.
REDD: Antitesis Reboisasi?
160 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Sementara jika berpikir realistis diperlukan keseimbangan antarakonservasi, ekonomi, dan sosial.
Harapan pemerintah Propinsi Jambi, REDD dapat mendukungagenda pembangunan daerah dan mengakomodir kepentinganpengembangan ekonomi masyarakat terutama sekitar kawasan hutanyang akan dijadikan lahan REDD. Selain itu, REDD harus sesuaidengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.Artinya, perencanaan REDD yang saat ini sedang dilakukan, haruscermat sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan pihak-pihak terkait.
REDD: Antitesis Reboisasi?
161Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Apa yang Terjadi dan Bagaimana ke DepanKebijakan penghutanan kembali di berbagai belahan Indonesia
telah memiliki sejarah panjang. Berangkat dari pemahaman awalbahwa hutan hanyalah bernilai ekonomi semata, perlahan-lahandiskursus teoritik dan kebijakan kehutanan di Indonesia mulaimelihat nilai-nilai lain yang dikandung hutan sebagai sebuahhamparan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan. Nilaiekonomi kemudian berkembang menjadi nilai-nilai biodiversity,berlanjut dengan nilai-nilai dalam lingkup jasa lingkungan danterakhir, hutan kemudian dilihat dari pendekatan karbon yangmenjadi bagian penting dari perdebatan perubahan iklim.
Kegiatan penghutanan kembali hutan-hutan yang telah ter-deforestasi atau terdegradasi terus berlangsung di tengah hirukpikuknya kegiatan-kegiatan ekstraktif baik dalam lingkup kehutanansendiri maupun kegiatan-kegiatan di luar lingkup kehutanan yangmemerlukan kawasan hutan.
Setelah tim studi melakukan penelitian singkat tentang bagaimanaprogram penghutanan kembali dilaksanakan di lapangan, tim studimasing-masing propinsi (Riau, Sumbar, dan Jambi) menghasilkankesimpulan sebagai berikut :
4.1. Riau4.1.1. Apa yang Terjadi?
1. Paradigma yang dipakai dalam pengelolaan hutan di Riaumasih menggunakan paradigma eksploitatif. Kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan hutan masih belummemperhatikan aspek sustainibilitas sumber daya hutan.Berbagai aktivitas investasi bidang kehutanan danpertambangan telah menimbulkan dampak lingkungan yangmengancam kelestarian ekosistem, seperti terjadinyabentang alam dan hilangnya spesies. Ada sedikit pergeseran
REDD: Antitesis Reboisasi?
165Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
yang berarti dalam pola kebijakan kehutanan di Indonesiapada era reformasi dibandingkan dengan era sebelumnya,terutama dalam soal pelibatan masyarakat dalampengelolaan hutan. Namun, pada dataran praktis kebijakantersebut belum dipraktekkan maksimal;
2. Kebijakan perlindungan hutan tidak sebanding dengankebijakan eksploitasi sumber daya hutan. Lajunya aruskebijakan perlindungan hutan tidak sebanding dengankebijakan yang mengarah pada eksploitasi kawasan hutan;
3. Kegagalan proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan diPropinsi Riau dikarenakan manajemen pengelolaan yangtidak baik. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lainmanajemen pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal.Pengelolaan dana dan pengorganisasian kegiatanmerupakan pangkal masalah kegagalan proyek GN-RHLdi Kuntu; Bibit yang ditanam terlalu kecil, bahkan sebagianbibit ditemukan tidak ditanam, minimnya pelibatan wargadan organisasi masyarakat setempat sebagai mitra utamadalam pelaksanaan proyek, tidak adanya insentif ekonomiyang dapat merangsang partisipasi masyarakat dalamkegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu baik saatproyek dilaksanakan maupun setelahnya, dan tidak adanyapengawasan setelah aktivitas penanaman selesai dilakukan;
4. Ditemukan kearifan lokal dalam masyarakat kawasan hutandalam mengelola sumber daya hutan. Meski demikiandisadari bahwa tidak semua masyarakat di kawasan hutanRimbang Baling melakukan praktik pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal, bahkanbanyak diantaranya yang mulai mengendur kebanggaannyaterhadap aturan-aturan adat dan nilai-nilai tradisional yangdianut sebelumnya, sehingga perlu fasilitasi pelbagai pihakdalam rangka reaktualisasi nilai-nilai dan kearifan tradisionaldalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.
REDD: Antitesis Reboisasi?
166 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
4.1.2. Bagaimana ke DepanBerdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimanadikemukakan di atas, maka penelitian ini merekomen-dasikan beberapa hal sebagaimana berikut :
1) Penghentian atau penangguhan Izin. Diperlukan sikappolitik pemerintah untuk melakukan penghentian terhadappengrusakan kawasan hutan dengan moratorium ijininvestasi baru, sekaligus meminta pertanggungjawabanpihak-pihak yang telah melakukan pengrusakan;
2) Pengelolaan hutan berbasis kemitraan. Penyelenggaraankegiatan kehutanan harus dilakukan secara terpadu, denganselalu menjalin kemitraan berbagai pihak. Kemitraan iniakan menghindarkan diri dari pendekatan sektoral.Kemitraan dengan masyarakat dalam melakukan proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan berkorelasi positifdengan tingkat keberhasilan program tersebut;
3) Reformasi kebijakan di bidang kehutanan. Pengelolaan yangbersifat sektoral cenderung menimbulkan monopoli yangberakibat pada marginalisasi hak-hak masyarakat, selainpenghancuran kawasan secara sistematis. Oleh karena itu,kebijakan pengelolaan kehutanan harus mengedepankanpertimbangan aspek kelestarian dan keberlanjutan, dengantetap memenuhi rasa keadilan antar generasi;
4) Penegakan Hukum. Jaminan kelestarian dan keberlanjutanfungsi hutan, baik ekologi, ekonomi, dan sosial memerlukandukungan komitmen para pihak dalam penegakan hukum.Kontrol kuat dari masyarakat harus ditumbuhkan untukmeminimalisir berkembangnya tindak pidana korupsi dankolusi antara penegak hukum dan pelanggar hukum;
5) Penghargaan Kearifan Lokal. Salah satu penyebab tingginyalaju kerusakan hutan Riau di kawasan Rimbang Baling danmusnahnya beberapa jenis keanekaragaman hayati(biodiversity) adalah absennya pengakuan negara terhadap
REDD: Antitesis Reboisasi?
167Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
etika dan kearifan lokal. Penyeragaman pemberlakuanhukum dalam sistem pengelolaan hutan telah secara nyatamematikan inisiatif masyarakat. Revitalisasi kearifan lokal,sekaligus pengakuan negara atas kearifan tersebut, harusmenjadi bagian dari upaya penyelamatan hutan.
4.2. Sumatera BaratTantangan yang terbesar dalam memecahkan masalahdegradasi dan deforestasi hutan tampaknya tetap saja masihterkait dengan politik hukum dari kebijakan kehutanan itusendiri. Sebagian dari kebijakan hutan secara politik hukumternyata masih mengabaikan praktek-praktek pengelolaanhutan berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini persoalanutamanya masih berhubungan dengan lemahnya pengakuanterhadap hak-hak adat baik dalam kepemilikan, penguasaan,dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam kebijakankehutanan nasional.Tidak hanya itu, kebijakan kehutanan di tingkat daerahumumnya ternyata juga masih tergantung pada kebijakanpemerintah pusat. Minim sekali inisiatif dan kreatifitaspemerintahan daerah dalam mendukung kebijakankehutanan yang lebih sesuai dengan keadaan-keadaan lokal.Kalaupun ada upaya yang dilakukan untuk melibatkanpartisipasi masyarakat, ternyata yang terjadi pun masihberupa partisipasi semu (shadow participatory).Berdasarkan studi politik hukum atas kebijakan kehutanandan pelaksanaan GN-RHL di Propinsi Sumatera Barat ini,ke depan kiranya perlu memperkuat pengelolaan hutanberdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di nagariuntuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.
4.3. JambiSudah cukup banyak inisiatif perlindungan dan pengelolaan
REDD: Antitesis Reboisasi?
168 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
hutan di Propinsi Jambi terutama yang berbasis masyarakatdinilai cukup efektif mempertahankan fungsi ekosistemkawasan hutan. Secara yuridis pengelolaan hutan berbasismasyarakat masih memiliki kelemahan yuridis yaknikepastian hukum pengelolaan hutan berbasis masyarakat.Sementara konsep REDD merupakan tawaran yangmenggiurkan bagi pemerintah, sehingga diupayakan untukdiperkuat dari sisi yuridis.Kedua konsep ini sesungguhnya merupakan alternatifuntuk perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan diIndonesia. Untuk itu beberapa rekomendasi yang alternatiftersebut sebagai berikut:
1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dan hutan desasecara lestari dan berkeadilan, mutlak memerlukankelembagaan ekonomi yang kuat dan dukungan kebijakanyang baik. Dalam hal langkah-langkah yang sangat mungkindilakukan adalah :a. Guna mendukung usaha kehutanan, desa membentuk
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undangNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Pasal 213 ayat (1) : Desa dapat mendirikan badan usahamilik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.Ketentuan ini merupakan peluang yang selama inibelum dimanfaatkan oleh desa dalam meningkatkanpendapatan desa;
b. Dukungan kebijakan yang diharapkan dari pemerintahpusat adalah secara tegas memberikan kepastiankewenangan bagi desa untuk mengelola dan meman-faatkan hutan adat dan hutan desa secara mandiri.Dalam hal ini bisa dilakukan melalui perbaikan danpengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentangHutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Agar tidakmenjadi kendala, beberapa prinsip yang perlu
REDD: Antitesis Reboisasi?
169Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
diakomodir diantaranya tentang prasyarat pengakuanmasyarakat hukum adat harus memperhatikan kondisiaktual masyarakat di sekitar hutan saat ini, yaknikesatuan komunitas berdasarkan rumpun adat;
c. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dapatdilakukan dengan cara memasukkan hutan adat danhutan desa sebagai program dalam Rencana StrategisDaerah (Renstra), Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten dan Provinsi (RTRWK/P). Di sampingakan mengikat secara formal, juga mengikat komitmenpemerintah daerah dalam pengelolaan hutan berbasismasyarakat masa kini dan akan datang.
2. Berkaitan dengan REDD:a. Secara nasional diperlukan kebijakan mengenai hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangkaperencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi REDD. Hal ini untukmengakomodir keterlibatan pemerintah daerah ataspengelolaan taman nasional. Kebijakan ini tidak hanya dalamrangka REDD, namun dalam kerangka pengelolaan tamannasional pada umumnya;
b. Berkaitan dengan pembagian kewenangan tersebut,diperlukan alokasi pendanaan REDD yang proporsional pula.Hal ini sesuai dengan norma dalam penyelenggaraanpemerintahan, bahwa penyerahan sebuah urusan harus diikutidengan pendanaan yang sesuai dengan besar kecilnya urusanyang diberikan;
c. Keterlibatan masyarakat atas program REDD di daerah harusdidorong dan diakomodir. Tidak seperti skema yang saat inimenjadi pola pikir pemerintah (departemen kehutanan/balaitaman nasional), bahwa keterlibatan masyarakat cukupdilakukan secara pasif yakni : tidak melakukan aktivitas ataumengganggu kawasan Taman Nasional. Maka masyarakat akan
REDD: Antitesis Reboisasi?
170 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
diberikan insentif dalam rangka pengentasan kemiskinan.Namun lebih dari itu, masyarakat harus diberikan hak dankewajiban atas pengelolaan Taman Nasional. Mekanisme kerjasama antara kelembagaan masyarakat dengan Balai TamanNasional perlu diatur kembali;
d. Permenhut No. 30 Tahun 2009 harus kembali direvisi, karenahal-hal yang dikemukakan di atas belum diatur secara jelas.Hal ini penting, mengingat saat ini Permenhut tersebut satu-satunya instrumen hukum terendah dan konkrit yangdijadikan pedoman bagi pemerintah untuk pelaksanaanREDD. Dan masih ada kesempatan untuk melakukan revisitersebut, menjelang rangkaian akhir persiapan menujuimplementasi REDD tahun 2012;
e. Di tingkat desa, fasilitasi kerja sama antar desa mutlakdilakukan, mengingat selama ini berbagai aktivitas baik yangdilakukan oleh pemerintah/daerah maupun NGO belumsecara langsung menghubungkan kepentingan-kepentinganbersama desa-desa tersebut atas Taman Nasional Berbak(TNB). Wujud kerja sama antar desa ini bisa saja dalam bentukperaturan bersama antar desa dalam rangka pengelolaan TNB.
REDD: Antitesis Reboisasi?
171Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Daftar PustakaArdi Andono, Pemanfaatan Flora dan Fauna dari Kawasan Konservasi,
BKSDA Jabar, 2003.
Barr, Christopher, Ahmad Dermawan, Herry Purnomo, dan HeruKomarudin, Financial governance and Indonesia’s Reforestation Fundduring the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: A politicaleconomic analysis of lessons for REDD+, (Bogor, CIFOR, 2010)
Budidaya, Peluang Implementasi REDD (Reducing Emissions fromDeforestation and Degradation) di Provinsi Jambi, Makalah, Jambi,2008.
Climate Action Network (CAN), Pengurangan Emisi dari Deforestasidan Degradasi (REDD), Dokumen Diskusi, 2007.
Collins, Elizabeth Fuller, Indonesia Dikhianati, (Jakarta: Gramedia,2008)
DTE, Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan, KIPPY PrintSolution, 2009.
FWI, 2004. Sejarah Penjarahan Hutan Nasional, Intip Hutan | Februari2004
Hardjosentono, H.P. Kata Sambutan, dalam Soewardi, H. 1978.
Ibrahim, Tengku Haji, dan Muhammad Isa, Sejarah Adat IstiadatKampar Kiri, Manuskrip tidak dipublikasikan, Kerajaan GunungSahilan, 1939.
Institute for Global Environmental Strategies, Panduan Kegiatan MPBdi Indonesia, 2005.
Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani, Politik Lingkungan danKekuasaan di Indonesia, (Jakarta: Equinox Publishing, 2006)
REDD: Antitesis Reboisasi?
173Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Kartodihardjo, hariadi & Agus Supriono. Dampak PembangunanSektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: KasusPembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia, CIFOR, OccasionalPaper No. 26(I), Jan. 2000
Kleden, Emilianus Ola, Liz Chidley, Yuyun Indradi (ed.), Forests forthe Future: Indegenous Forest Management in a Changing World,(Jakarta: Down to Eart & AMAN, 2009)
Kemenhut. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Statistik KehutananIndonesia 2008. 2009
Mulyati Rahayu, et., all., Kajian Pemanfaatan Tumbuhan Hutan NonKayu oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi PT. Wira KaryaSakti Sungai Tapa – Jambi Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi,Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor Desember2006.
P.Warsito. Sofyan, Dana Reboisasi (DR) sebagai sumber danapembinaan hutan di areal kerja IUPHHK (HPH) Tidak kahBoleh ?
Prianto Wibowo, Pemantauan Hutan Rawa Gambut di Kawasan Berbak-Sembilang, Wetlands Internasional-Indonesia Programme.
Putro, H.R., Participatory Management of National Park and ProtectionForest: a New Challenge in Indonesia, online, http://www.nou-rishin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdf diaksesFeb/2010., 2001
Riokasyterwandra dan Zulbakri Oemala, Musyawarah MasyarakatAdat Antau Singingi, Pekanbaru: Lembaga Adat Antau Singingi,2007
Suhana, Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung,Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Pengelolaan danPerlindungan Lingkungan Hidup, http://pk2pm.files.word-
REDD: Antitesis Reboisasi?
174 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
press.com/2010/01/pengakuan-kearifan-lokal-lubuk-larangan-indarung.pdf Downlod tanggal 5 Maret 2010.
Soewardi, H., Menyongsong Taman Nasional (National Park) di Indonesia,Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, DirektoratJenderal Kehutanan, 1978.
Sudariyono, Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut di Tingkat Nasionaldan Internasional, Makalah Seminar, Jakarta, 2004.
Sulistiyanto, Case Studies on Peatland Use Their Impacts-The IndonesianExperience (Experience in Sumatra dan Kalimantan), Faculty ofAgriculture, University of Palangka Raya, diakses Feruari 2010.
UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO), NationalConservation Plan for Indonesia Volume III, laporan lapangandisediakan untuk Direktorat Perlindungan dan PengawetanAlam, Direkturat Jenderal Kehutanan, Bogor, 1981.
Wiryono, P. Kata Pengantar, dalam Widianarko, B., Ekologi dan KeadilanSosial, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
White, Ben, Land and resouce tenure: brief notes, Paper presented atinternational Conference on Land Resource Tenure in Indonesia:Questioning The Answer
WWF., Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca?.,Lembar Fakta, diakses Februari 2010.
Media Online
Gibbon Indonesia. Edan! 1,1 Juta Hektar, Laju Kerusakan HutanIndonesia, Jumat, 27 November 2009 00:00, http://www.gibbon-indonesia.org/index.php?option= com_con-tent&view=article&id=67%3Aedan-11-juta-hektar-laju-kerusakan-hutan-indonesia&catid=3%3Aberita-lingku-ngan&Itemid=1&lang=en
REDD: Antitesis Reboisasi?
175Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
_________Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia, Monday, October25, 2004 http://kumpulanperkarakorupsi.blogspot.com/2008/08/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html
Kaban,M.S., Progres Kebijakan Departemen Kehutanan Lima TahunTerakhir Senin, 31 Agustus 2009, (http://www.setneg.go.id /index.php?option =com_content&task=view&id=3936&Itemid=286)
Kompas, “Pembalakan Liar Hanya 26 Persen: Selama 9 TahunDibuka 1 Juta Ha Hutan di Riau”, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10/03191280/ download tanggal 11 April2010.
________Laporan Pembinaan Perencanaan Program Penghijauan DanReboisasi, http://regionaldua.tripod.com/hijau.html,
Raflis, Peta Rencana Pembuatan Jalan di SM Bukit RimbangBukit Baling, dikutip dalam http://raflis.wordpress.com/2009/05/17/peta-rencana-pembuatan-jalan-di-sm-bukit-rimbang-bukit-baling/ download tanggal 5 Maret 2010.
Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Rimbang Bukit Baling,http://www.kuansing.go.id/141/20090120/rencana-pengembangan-kawasan-wisata-bukit-rimbang-bukit-baling-kabupaten-kuantan-singingi/2/ download pada tanggal 25Februari 2010.
WawancaraBustamir, Khalifah Kuntu, Kampar Kiri, 7-12 Maret 2010.Iskandar, Tokoh Masyarakat Pangkalan Indarung, 12-13 Maret 2010Japri, Tokoh Adat Kuntu, Kuntu, 7-8 Maret 2010Yusman, Ketua Adat Batu Sanggan, 10 Maret 2010.
REDD: Antitesis Reboisasi?
176 Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
Lampiran 1
DAFTAR KAWASAN KONSERVASI DI RIAU YANGTERANCAM AKIBAT ILLEGAL LOGGING DAN
PERAMBAHAN UNTUK PEMBANGUNANPERKEBUNAN SAWIT
REDD: Antitesis Reboisasi?
177Scale Up - Sustainable Social Development Partnership