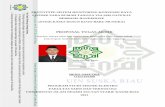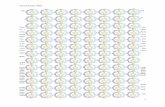PROPOSAL TUGAS AKHIR
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of PROPOSAL TUGAS AKHIR
Pemilihan Subsektor Kerajinan Unggulan
Sebagai Dasar Perumusan Strategi
Pengembangannya di Kabupaten Bangkalan
Proposal Skripsi
Disusun Untuk Melengkapi Tugas Dan Menempuh Persyaratan
Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Dan Menempuh Gelar
Sarjana Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura
Diajukan Oleh:
SITI MUHIMATUL KHOIROH
10.04.211.00043
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tuntutan perekonomian di era sekarang ini
mengharuskan setiap orang ataupun perusahaan berfikir
kreatif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya
dalam meghadapi persaingan global. Dalam
perkembanganya, perekonomian di Indonesia juga telah
berkembang industri kreatif diaman dalam pelaksanaanya
kreatifitas dan inovasi adalah kunci utama untuk
mejalankannya. Menurut Departemen Perdagangan Republik
Indonesia dalam buku “ Pengembangan Ekonomi Kreatif
Indonesia 2025” (2008: 23), keberadaan sektor industri
kreatif yang bermunculan diberbagai daerah di Indonesia
memiliki kontribusi yang signifikan bagi perekonomian
Indonesia, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif,
dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia,
mendukung pemanfaatan sumber daya terbarukan, merupakan
pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas,
dan memiliki dampak sosial yang positif.
UK DCMS Task Force 1998, dalam buku Pengembangan
Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (2008 : 4) menyatakan
bahwa industri kreatif adalah industri-industri yang
mana dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing
kreativitas individual, ketrampilan dan bakat yang
berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan
kesejahteraan bagi para anggotanya dari generasi ke
generasi melalui kemampuan daya cipta individu dalam
industri itu sendiri. Ekonomi kreatif terdiri dari
periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain,
fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan,
penelitian dan pengembangan (R&D), perangkat lunak,
mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan
radio (Howkinds John : 2002).
Menurut John Howkins dalam bukunya “The Craetive
Economy, How People make Money from Ideas,” (Penguin Books,
2002) mengelompokkan 15 (lima belas) kelompok industri
yang termasuk industri kreatif yakni 1) Advertising, 2)
Architecture, 3) Art, 4) Craft, 5) Design, 6) Fashion,
7) Film, 8) Music, 9) Performing Arts, 10) Publishing,
11) R&D, 12) Software, 13) Toys and Games, 14) TV &
Radio, 15) Video Games. Sedangkan Industri kreatif yang
berbasis kreativitas oleh Departemen Perdagangan RI
dikelompokkan menjadi empat belas sektor yaitu
periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik,
kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi,
permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti
lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan
(Sumotarto Untung, 2010). Dari kedua teori
pengelompokan tersebut ternyata memiliki kesamaan hanya
berbeda pada poin toys and games yang dalam klasifikasi
Howkins dijadikan satu kelompok.
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah di
Jawa Timur yang meliki banyak IKM yang sudah terdaftar
di Dinas Perdagangan setempat. Dari banyaknya IKM dari
setiap sektor industri kreatif yang ada belum
difokuskan sektor industri yang mana yang merupakan
sektor unggulan sehingga belum adanya fokus pemerintah
untuk memberikan perhatian lebih agar sektor tersebut
dapat lebih dikembangkan untuk kemajuan masyarakat dan
pendapatan daerah Bangkalan.
Menurut Pradana (2013), subsektor kerajinan
merupakan sektor industri kreatif yang merupakan
kompetensi inti daerah Bangkalan yang paling banyak
diminati dibandingkan dengan sektor yang lainnya.
Selain itu, berdasarkan penelitian Indahsari Kurniyati
(2010), dengan menggunakan metode scoring menyatakan
bahwa ternyata industri yang menjadi kompetensi daerah
Bangkalan adalah industri tali agel, pecut, anyam
tikar, sangkar burung dan selebihnya adalah yang
berbahan dasar sumber daya alam seperti petis dan
kerupuk terung. Hasil penelitian lain yang menunjukkan
bahwa sektor kerajinan adalah sektor unggulan dan
kompetensi inti di Kabupaten Bangkalan adalah
penelitian Narita Putri (2010) dengan tema penelitian
pemilihan proritas pengembangan sektor industri kecil
yang menegaskan bahwa industri kerajinan merupakan
sektor yang direkomendasikan untuk dikembangkan.
Berdasarkan ketiga penelitian Narita Putri (2010),
Indahsari Kurniyati (2010) dan Pradana (2013),
peneliti berupaya melakukan penelitian lanjutan sebagai
bentuk tindak lanjut terhadap hasil penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa sektor kerajinan
adalah sektor unggulan di Kabupaten Bangkalan. Dengan
penelitian ini peneliti mencoba menggali lebih spesifik
dari beberapa subsektor kerajinan seperti emban cincin,
gedek, kusen kayu, kerajinan batu-batuan, pecut, perahu
kayu, perhiasan, meubel dan tikar yang merupakan
subsektor unggulan di Kabupaten Bangkalan dengan
menggunakan metode pembobotan AHP. Selanjutnya
dilakukan pembuatan rantai nilai untuk menjelaskan alur
proses penciptaan nilai yang terjadi dalam industri
kreatif unggulan sekaligus membantu stakeholder industri
kreatif untuk memahami posisi industri kreatif unggulan
yang terkait dengan kreasi, produksi, distribusi dan
komersialisasi dalam bentuk mapping . Tidak berehenti
sampai pada pembuatan rantai nilai, namun penelitian
ini berlanjut pada perumusan strategi pengembangan .
Dengan berdasarkan value chain mapping tersebut dilakukan
pembobotan dengan metode ANP (Analytical Hierarchy Process). ANP
merupakan sebuah metode yang digunkaan untuk
menyelesaikan permasalahan Multy Criteria Decision Making
(Saaty 2006; Singgih 2009). Metode ini digunakan untuk
merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai
alternatif solusi berdasarkan pertimbangan keterkaitan
antar kriteria dan sub kriteria yang ada (Saaty, 2006;
Sapto, 2008; Suswono, 2010).
Oleh karena itu, berdasrkan latar belakang diatas
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini
sebagai syarat penyelesaian studi sekaligus sebagi
langkah continuious research agar penelitian sebelumnya
dapat dikembangkan dalam sebuah laporan yang berjudul
“Pemilihan Subsektor Kerajinan Unggulan Sebagai Dasar
Perumusan Strategi Pengembangnnya di Kabupaten
Bangkalan”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
memilih subsektor unggulan pada sektor industri
kreatif kerajinan dan merumuskan strategi
pemngembangannya.
1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini antara lain :
1. Mendapatkan subsektor kerajinan unggulan pada
industri kreatif di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengidentifikasi rantai nilai (value chain) industri
kreatif unggulan dari sektor kerajinan yang ada di
Bangkalan.
3. Membuatkan rumusan strategi pengembangan untuk
subsektor kerajinan unggulan di Bangkalan.
4. Menganalisis startegi paling tepat untuk industri
kreatif unggulan sektor kerajinan di Bangkalan
menggunakan metode ANP.
1.4 Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara
lain sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran tentang Industri Kreatif
subsektor kerajinan unggulan yang ada di Bangkalan
bagi Desperindag kabupaten Bangkalan.
2. Memberikan informasi strategi pemasaran bagi
pemerintah Bangkalan untuk meningkatkan sektor IKM
di Bangkalan sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah Bangkalan dan memperluas
jangkauan sektor unggulan yang ada di Bangkalan.
1.5 Batasan
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Data yang digunakan adalah data sektor kerajinan
di Bangkalan.
2. IKM yang diteliti hanya yang terdaftar di
Desperindag
1.6 Asumsi
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Industri kecil menengah yang menjadi alternatif
dalam penelitian ini terus berjalan hingga
penelitian ini berakhir.
2. Tidak ada perubahan kebijakan yang berarti selama
penelitian berlangsung untuk industri kreatif
khususnya sektor kerajinan
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penulisan laporan
penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, batasan masalah, asumsi penelitian
dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi teori-teori dari berbagai sumber
tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan
sebagai landasan dalam penentuan topik
permasalahan yang akan dilakukan. Sumber teori
bisa didapatkan dari buku, internet, maupun
nara sumber yang terkait dengan penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN
Berisi tentang objek dan lokasi penelitian,
populasi dan sampel penelitian, Jenis data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, dan
metode analisis data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang pengolahan data, hasil analisis
data dan pembahasannya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan dari hasil
penelitian yang dapat menjawab tujuan
dilaksanakannya penelitian disertai saran-
saran yang membangun.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Industri Kreatif
Pengertian Industri kreatif muncul seiring dengan
perkembangan evolusi perekonomian dunia. Menurut
Hesmondhalgh, David (2002) The Cultural Industries, Industri
Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas
ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan
pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga
dikenal dengan nama lain Industri Budaya (terutama di
Eropa atau juga Ekonomi Kreatif . Menurut John Howkins
dari buku “The Creative Economy: How People Make Money from
Ideas”, Ekonomi Kreatif terdiri dari periklanan,
arsitektur, seni, kerajinan. desain, fashion, film,
musik, seni pertunjukkan, penerbitan, Penelitian dan
Pengembangan (R&D), perangkat lunak, mainan dan
permainan, Televisi dan Radio, dan Permainan Video.
Definisi Industri Kreatif berdasarkan UK DCMS Task
Force 1998 dalam buku “ Pengembangan Ekonomi Kreatif
Indonesia 2025” , industri kreatif adalah “Creative
Industries as those industries which have their origin in individual
creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job
creation through the generation and exploitation of intellectual property
and content”. Departemen Perdagangan Republik Indonesia
sendiri telah melakukan studi pemetaan terhadap
industri kreatif yang ada di Indonesia pada tahun 2007
dengan menggunakan acuan definisi industri kreatif yang
sama, yaitu “ Industri yang berasal dari pemanfaatan
kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya
cipta individu tersebut”.
Berdasarkan beberapa devinisi diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa industri keratif adalah industri yang
memanfaatkan kemampuan setiap individu baik
kreativitas, ketrampilan serta bakat daya cipta yang
dimiliki untuk membangun lapangan pekerjaan dan
kesejahteraan anggotanya dengan informasi dan
pengetahuan yang dimiliki.
2.2 Sektor-Sektor dalam Industri Kreatif Indonesia
Menurut John Howkins dalam bukunya “The Craetive
Economy, How People make Money from Ideas,” (Penguin Books,
2001) mengelompokkan 15 (lima belas) kelompok industri
yang termasuk industri kreatif yakni 1) Advertising, 2)
Architecture, 3) Art, 4) Craft, 5) Design, 6) Fashion,
7) Film, 8) Music, 9) Performing Arts, 10) Publishing,
11) R&D, 12) Software, 13) Toys and Games, 14) TV &
Radio, 15) Video Games.
Sedangkan Industri kreatif yang berbasis
kreativitas oleh Departemen Perdagangan RI
dikelompokkan menjadi empat belas sektor yaitu
periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik,
kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi,
permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti
lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan
(Sumotarto Untung, 2010). Dari kedua teori
pengelompokan tersebut ternyata memiliki kesamaan hanya
berbeda pada poin toys and games yang dalam klasifikasi
Howkins dijadikan satu kelompok.
Berikut ini penjelasan lebih detail dari ke-14
sektor industri kreatif berdasarkan ketentuan
Departemen Perdagangan RI (2008):
1. Periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi dan produksi iklan, antara lain: riset pasar,
perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang,
produksi material iklan, promosi, kampanye relasi
publik, tampilan iklan di media cetak dan
elektronik.
2. Arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
cetak biru bangunan dan informasi produksi antara
lain: arsitektur taman, perencanaan kota,
perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan
warisan, dokumentasi lelang, dll.
3. Pasar seni dan barang antik: kegiatan kreatif yang
berkaitan dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan,
produk antik dan hiasan melalui lelang, galeri,
toko, pasar swalayan, dan internet.
4. Kerajinan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi dan distribusi produk kerajinan antara lain
barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga,
aksesoris, pandai emas, perak, kayu, kaca, porselin,
kain, marmer, kapur, dan besi.
5. Desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi
desain grafis, interior, produk, industri,
pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan.
6. Desain Fesyen: kegiatan kreatif yang terkait dengan
kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain
aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan
aksesorisnya, konsultansi lini produk fesyen, serta
distribusi produk fesyen.
7. Video, Film dan Fotografi: kegiatan kreatif yang
terkait dengan kreasi produksi Video, film, dan jasa
fotografi, serta distribusi rekaman video,film.
Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film,
sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.
8. Permainan interaktif: kegiatan kreatif yang
berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi
permainan komputer dan video yang bersifat hiburan,
ketangkasan, dan edukasi.
9. Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman
suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis
lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik,
penyanyi, dan komposisi musik.
10. Seni Pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan
dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan
konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet,
tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik
tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik
etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata
panggung, dan tata pencahayaan.
11. Penerbitan &Percetakan : kegiatan kreatif yang
terkait dengan dengan penulisan konten dan
penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid,
dan konten digital serta kegiatan kantor berita.
12. Layanan Komputer dan piranti lunak: kegiatan
kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi
informasi termasuk jasa layanan komputer,
pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain
dan analisis sistem, desain arsitektur piranti
lunak, desain prasarana piranti lunak & piranti
keras, serta desain portal.
13. Televisi & radio: kegiatan kreatif yang berkaitan
dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan,
penyiaran, dan transmisi televisi dan radio.
14. Riset dan Pengembangan: kegiatan kreatif yang
terkati dengan usaha inovatif yang menawarkan
penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan
pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan
kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat
baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat
memenuhi kebutuhan pasar.
2.3 Indikator Pemetaan Industri Kreatif di Indonesia
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua
barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah
tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya
pertahun). PDB berbeda dari Produk Nasional Bruto
karena memasukkan pendapatanfaktor produksi dari luar
negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB
hanya menghitung total produksi dari suatu negara
tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan
dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau
tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor
produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga
Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan
pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB
Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB
nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB
dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu
pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.
Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran
adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor - impor
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang
dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor
usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, ekspor
dan impor melibatkan sector luar negeri, sementara
pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang
diterima factor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + labaDi mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor
produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenagakerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untukpengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatanpengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angkayang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDBdengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, makayang sering digunakan adalah dengan pendekatanpengeluaran (Wikipedia, 2007)
2.3.2 Ketenagakerjaan
Jumlah Tenaga Kerja (Employement Number) adalah
angka yang menunjukkanjumlah pekerja tetap yang berada
pada seluruh lapangan pekerjaan/usaha diindustri
kreatif. Sesuai dengan definisi Badan Pusat Statistik,
pekerja tetapadalah mereka yang bekerja lebih besar
dari 35 jam seminggu, sebelum survey ketenagakerjaan
dilakukan. Semakin besar Jumlah Tenaga Kerja, secara
relative dapat mengindikasikan semakin penting peranan
industri kreatif dalam perekonomian.
2.3.3 Perdagangan Internasional
Perdagangan Internasional dapat diartikan
sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi
negara yang satu dengan subyek ekonomi negara
yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa.
Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk
yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan
ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri,
perusahaan negara ataupun departemen pemerintah.
Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan
sebagai proses tukar menukar yang didasarkan
atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.
Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk
menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut,
dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian
menetukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau
tidak (Boediono, 2000). Pada dasarnya ada dua teori
yang menerangkan tentang timbulnya perdagangan
internasional.
2.3.4 Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan adalah jumlah firm yang ada di
setiap kelompokindustry kreatif. Misalnya, jumlah
perusahaan periklanan di industri
periklananIndonesia. Semakin besar nilai indikator
jumlah perusahaan (Number of Firm)dalam suatu industri,
maka semakin dekat karakteristik pasar/industri
kepadapasar persaingan sempurna, semakin tinggi
intensitas persaingan, dankesejahteraan yang terjadi
di pasar/industri akan semakin besar.
Denganmembandingkan angka jumlah perusahaan ini
dengan total jumlah perusahaandalam industri, serta
angka penyerapan tenaga kerjanya, dapat
mengindikasikanbesarnya peran industri kreatif dalam
perekonomian nasional.Total jumlah perusahaan yang
terlibat dalam 14 lapangan usaha merupakan JPatau NoF
industri kreatif.
2.4 Kerajinan
Jumlah perusahaan adalah jumlah firm yang ada di
setiap kelompokindustry kreatif. Misalnya, jumlah
perusahaan periklanan di industri periklananIndonesia.
Semakin besar nilai indikator jumlah perusahaan (Number
of Firm)dalam suatu industri, maka semakin dekat
karakteristik pasar/industri kepadapasar persaingan
sempurna, semakin tinggi intensitas persaingan,
dankesejahteraan yang terjadi di pasar/industri akan
semakin besar. Denganmembandingkan angka jumlah
perusahaan ini dengan total jumlah perusahaandalam
industri, serta angka penyerapan tenaga kerjanya, dapat
mengindikasikanbesarnya peran industri kreatif dalam
perekonomian nasional.Total jumlah perusahaan yang
terlibat dalam 14 lapangan usaha merupakan JP atau NoF
industri kreatif.
2.5 Rantai Nilai (Value Chain)
Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia
dalam buku “ Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia
2025” (2008: 81), Rantai nilai
yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rantai proses
penciptaan nilai yang umumnya terjadi di industri
kreatif. Pada industri kreatif biasanya rantai nilai
cenderung dalam hal bagaimana mengatur input berupa
akuisi dan konsumsi produk-produk fisikal sebagai
sumber dayanya (bahan baku). Sedangkan rantai nilai
yang berkaitan dengan industri kreatif yang
mengutamakan desain dalam proses produksinya lebih
mengarah pada pemanfaatan daya cipta atau
kreatifitas individunya. Dengan rantai nilai akan
mempermudah bagi stakeholder industri kreatif untuk
memahami posisi industri kreatif sehingga
mempermudah fokus pengembangannya yang terdiri dari
empat faktor yaitu kreasi, produksi, distribusi dan
komersialisasi seperti pada gambar berikut:
2.6 AHP
Analytical Hierarchy Process (AHP) atau Proses Hirarki
Analitik dalam buku “ Proses Hirarki Analitik Dalam
Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang
Kompleks”(Saaty, 1986), adalah suatu metode yang
sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas
dalam ancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini
merumuskan masalah dalam bentuk hierarki dan masukan
pertimbangan– pertimbangan untuk menghasilkan skala
prioritas relatif. Dalam penyelesaian persoalan dengan
metode AHP dalam buku Saaty (1986) tersebut, dijelaskan
pula beberapa prinsip dasar Proses Hirarki Analitik
yaitu :
1. Dekomposisi. Setelah mendifinisikan permasalahan,
maka perlu dilakukan dekomposisi yaitu memecah
persoalan utuh menjadi unsur-unsurnya sampai yang
sekecil kecilnya.
2. Comparative Judgment. Prinsip ini berarti membuat
penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada
suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan
tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti
dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas
elemen-elemen.
3. Synthesis of Priority. Dari setiap matriks pairwise
comparison vector eigen-nya mendapat prioritas lokal,
karena pairwise comparison terdapat pada setiap
tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan
sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan
sintesis berbeda menurut bantuk hirarki.
4. Logical Consistency. Konsistensi memiliki dua makna yang
pertama bahwa obyek-obyek yang serupa dapat
dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya.
Kedua adalah tingkat hubungan antar obyek-obyek yang
didasarkan pada kriteria tertentu.
Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat
analisis adalah :
1. Dapat memberi model tunggal yang mudah dimengerti,
luwes untuk beragam persoalan yang tak
berstruktur.
2. Dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan
berdasarkan sistem dalam memecahkan persolan
kompleks.
3. Dapat menangani saling ketergantungan elemen–
elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan
pemikiran linier.
4. Mencerminkan kecendrungan alami pikiran untuk
memilah–milah elemanelemen suatu sistem dalam
berbagai tingkat belaian dan mengelompokan unsur-
unsur yang serupa dalam setiap tingkat.
5. Memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang
tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
6. Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-
pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan
berbagai prioritas.
7. Menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang
kebijakan setiap alternatif.
8. Mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari
berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang
memilih alternatif terbaik berdasarkan
tujuantujuan mereka.
9. Tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis
suatu hasil representatif dari penilaian yang
berbeda-beda.
10. Memungkinkan orang memperluas definisi mereka
pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan
serta pengertian mereka melalui pengulangan.
AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai
masalah diantaranya untuk mengalokasikan sumber daya,
analisis keputusan manfaat atau biaya, menentukan
peringkat beberapa alternatif, melaksanakan perencanaan
ke masa depan yang diproyeksikan dan menetapkan
prioritas pengembangan suatu unit usaha dan
permasalahan kompleks lainnya
(http://www.itelkom.ac.id/ahp/library/1998).
Hirarki adalah alat yang paling mudah untuk
memahami masalah yang kompleks dimana masalah tersebut
diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan,
menyusun elemen-elemen tersebut secara hirarki dan
akhirnya melakukan penilaian atas elemen tersebut
sekaligus menentukan keputusan mana yang diambil.
Proses penyusunan elemen secara hirarki meliputi
pengelompokan elemen komponen yang sifatnya homogen dan
menyusunan komponen tersebut dalam level hirarki yang
tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu
sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara
komponen dan dampaknya pada sistem. Abstraksi ini
mempunyai bentuk yang saling terkait tersusun dalam
suatu sasaran utama (ultimate goal) turun ke sub-sub
tujuan, ke pelaku (aktor) yang memberi dorongan dan
turun ke tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan,
strategi-strategi tersebut. Adapun abstraksi susunan
hirarki keputusan seperti yang diperlihatkan pada
Gambar 2.1. berikut ini :
Level 1 : Fokus/sasaran/goal
Level 2 : Faktor/kriteria
Level 3 : Alternatif/subkriteria
Sedangkan kelemahan metode AHP adalah :
ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input
utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam
hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu
juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut
memberikan penilaian yang keliru.
Beberapa contoh aplikasi AHP adalah sebagai berikut:
1. Membuat suatu set alternatif.
2. Perencanaan, merancang system.
3. Menentukan prioritas.
4. Memilih kebijakan terbaik setelah menemukan satu set
alternatif.
5. Alokasi sumber daya dan memastikan stabilitas
sistem.
6. Menentukan kebutuhan/persyaratan.
2.6.1 Penentuan Prioritas dalam Metode AHP
Dalam pengambilan keputusan hal yang perlu
diperhatikan adalah pada saat pengambilan data, dimana
data ini diharapkan dapat mendekati nilai sesungguhnya.
Derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan dengan
pendekatan perbandingan berpasangan. Perbandingan
berpasangan sering digunakan untuk menentukan
kepentingan relatif dari elemen dan kriteria yang ada.
Perbandingan berpasangan tersebut diulang untuk semua
elemen dalam tiap tingkat. Elemen dengan bobot paling
tinggi adalah pilihan keputusan yang layak
dipertimbangkan untuk diambil. Untuk setiap kriteria
dan alternatif kita harus melakukan perbandingan
berpasangan (Pairwise comparison) yaitu membandingkan
setiap elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki
secara berpasangan sehingga nilai tingkat kepentingan
elemen dalam bentuk pendapat kualitatif.
Untuk mengkuantitifkan pendapat kualitatif
tersebut digunakan skala penilaian sehingga akan
diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka
(kualitatif). Menurut Saaty (1986) untuk berbagai
permasalahan skala 1 sampai dengan 9 merupakan skala
terbaik dalam mengkualitatifkan pendapat, dengan
akurasinya berdasarkan nilai RMS (Root Mean Square
Deviation) dan MAD (Median Absolute Deviation). Nilai dan
difinisi pendapat kualitatif dalam skala perbandingan
Saaty seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.1.
2.6.2 Proses-proses dalam Metode Analytical Hierarchy
Process (AHP)
Adapun Proses-proses yang terjadi pada metode AHP
adalah sebagai berikut (Saaty, 1986) :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang
diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum
dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan
alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.
3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang
menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh
setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat di
atasnya.
4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga
diperoleh judgment (keputusan) sebanyak n x ((n-
1)/2)bh, dengan n adalah banyaknya elemen yang
dibandingkan.
5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya
jika tidak konsisten maka pengambilan data
diulangi lagi.
6. Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk setiap
tingkatan hirarki.
7. Menghitung vector eigen dari setiap matrik
perbandingan berpasangan.
8. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih
dari 10 persen maka penilaian data judgment harus
diperbaiki.
2.6.3 Matrik Perbandingan Berpasangan
Skala perbandingan berpasangan didasarkan pada
nilai–nilai fundamental AHP dengan pembobotan dari
nilai 1 untuk sama penting sampai 9 untuk sangat
penting sekali sesuai dengan Tabel 2.1 (Skala Matrik
Perbandingan Berpasangan). Dari susunan matrik
perbandingan berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas
yang merupakan pengaruh relatif sejumlah elemen pada
elemen di dalam tingkat yang ada diatasnya. Perhitungan
eigen vector dengan mengalikan elemen-elemen pada setiap
baris dan mengalikan dengan akar n, dimana n adalah
elemen. Kemudian melakukan normalisasi untuk menyatukan
jumlah kolom yang diperoleh. Dengan membagi setiap
nilai dengan total nilai pembuat keputusan bisa
menentukan tidak hanya urutan ranking prioritas setiap
tahap perhitungannya tetapi juga besaran prioritasnya.
Kriteria tersebut dibandingkan berdasarkan opini setiap
pembuat keputusan dan kemudian diperhitungkan
prioritasnya. Perbandingan Kriteria berpasangan seperti
yang diperlihatkan pada Tabel 2.2.
2.6.4 Perhitungan Bobot Elemen
Perhitungan bobot elemen dilakukan dengan
menggunakan suatu matriks. Bila dalam suatu sub sistem
operasi terdapat ‘n” elemen operasi yaitu elemenelemen
operasi A1, A2, A3, ...An maka hasil perbandingan
secara berpasangan elemen-elemen tersebut akan
membentuk suatu matrik pembanding. Perbandingan
berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi,
dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan
perbandingan. Bentuk matrik perbandingan berpasangan
bobot elemen seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.3.
Bila elemen A dengan parameter i, dibandingkan dengan
elemen operasi A dengan parameter j, maka bobot
perbandingan elemen operasi Ai berbanding Aj
dilambangkan dengan Aij maka :
(ij) = Ai / Aj, dimana : i,j = 1,2,3,...n
Bila vektor-vektor pembobotan operasi A1,A2,... An
maka hasil perbandingan berpasangan dinyatakan dengan
vektor W, dengan W = (W1, W2,
W3....Wn) maka nilai Intensitas kepentingan elemen
operasi Ai terhadap Aj yang
dinyatakan sama dengan aij.
Dari penjelasan tersebut diatas maka matrik
perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrik), dapat
digambarkan menjadi matrik perbandingan preferensi
seperti diperlihatkan pada Tabel 2.4.
Nilai Wi/Wj dengan i,j = 1,2,…,n dijajagi dengan
melibatkan Responden yang memiliki kompetensi dalam
permasalahan yang dianalisis. Matrik perbandingan
preferensi tersebut diolah dengan melakukan perhitungan
pada tiap baris tersebut
dengan menggunakan rumus :
Wi = n√(ai1 x ai2 x ai3,….x ain)
Matrik yang diperoleh tersebut merupakan eigen vector
yang juga merupakan bobot kriteria. Bobot kriteria atau
Eigen Vektor adalah ( Xi), dimana :
Xi = (Wi / Σ Wi)
Dengan nilai eigan vector terbesar (λmaks)
dimana :
λmaks = Σ aij.Xj
2.6.5 Perhitungan Konsistensi Dalam Metode AHP
Matrik bobot yang diperoleh dari hasil
perbandingan secara berpasangan tersebut harus
mempunyai hubungan kardinal dan ordinal sebagai
berikut:
1. Hubungan Kardinal : aij – ajk = aik
2. Hubungan ordinal : Ai > Aj, Aj > Ak maka Ai > Ak
Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai
berikat :
a) Dengan melihat preferensi multiplikatif misalnya
keselamatan lalu lintas lebih penting 4 kali dari
kerusakan jalan, dan kerusakan jalan lebih penting
2 kali dari kemacetan maka keselamatan lalu lintas
lebih penting 8 kali dari kemacetan.
b) Dengan melihat preferensi trasitif, misalnya keselamatan
lalu lintas lebih penting dari kerusakan jalan dan
kerusakan jalan lebih penting dari kemacetan, maka
keselamatan lalu lintas lebih penting dari
kemacetan.
Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa
penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matrik
tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat
terjadi karena tidak konsisten dalam preferensi
seseorang, contoh konsistensi matrik sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar 2.2
Matrik A tersebut konsisten karena :
aij x ajk = aik ---- = 4 x ½ = 2
aik x akj = aij ---- = 2 x 2 = 4
ajk x aki = aji ---- = ½ x ½ = ¼
Permasalahan di dalam metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) pengukuran pendapat terhadap responden,
karena konsistensi tidak dapat dipaksakan. Pengumpulan
pendapat antara satu kriteria dengan kriteria yang lain
adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah
pada tidak konsistennya jawaban yang diberikan.
Pengulangan wawancara pada sejumlah responden
dalam waktu yang sama kadang diperlukan apabila derajat
tidak konsestennya atau penyimpangan terhadap
konsistensi dinilai besar.
Penyimpangan terhadap konsistensi dinyatakan
dengan indeks konsistensi didapat rumus :
Dimana :
Matrik random dengan skala penilaian 1 sampai
dengan 9 beserta kebalikannya sebagai Indeks Random
(RI). Dengan Indeks Random (RI) setiap ordo matriks
seperti diperlihatkan pada Tabel 2.5.
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 500
sampel, jika keputusan numerik diambil secara acak dari
skala 1/9, 1/8, ..,1, 2, …,9 akan memperoleh rata-rata
konsistensi untuk matriks dengan ukuran berbeda.
Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks
didefinisikan sebagai Ratio Konsistensi (CR). Untuk
model AHP matrik perbandingan dapat diterima jika nilai
ratio konsisten tidak lebih dari 10% atau sama dengan
0,1
2.6.6 Pembobotan Kriteria Total Responden
Pembobotan kriteria dari masing-masing responden
telah diperoleh
perhitungan dan dilanjutkan dengan menjumlahkan tiap
kriteria pada masingmasing responden. Nilai ini
kemudian dirata-ratakan dengan cara membaginya dengan
jumlah responden, seperti yang diperlihatkan pada Tabel
2.6.
Tabel 2.6 Rekapitulasi Bobot Seluruh Responden
2.7 ANP
Analytical Network Process (ANP) adalah suatu
teori pengukuran yang umumnya diaplikasikan pada
dominasi suatu pengaruh terhadap beberapa stakeholder
atau alternatif melalui suatu atribut atau kriteria
(Saaty, 2001). Menurut Profesor Thomas L. Saaty, pakar
riset dari Pittsburgh University, The Analytical
Network Process (ANP) adalah generalisasi dari
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan merupakan
pendekatan baru metode kualitatif, dengan
mempertimbangkan ketergantungan antara unsur-unsur
hirarki. Banyak masalah keputusan tidak dapat
terstruktur secara hierarki karena mereka melibatkan
interaksi dan ketergantungan unsur-unsur yang lebih
tinggi dalam hirarki di lower level elemen.
Menurut Saaty (1988), dengan jaringan hubungan
antara komponen dapat teridentifikasi melalui pemikiran
seseorang relatif tidak terikat oleh aturan. ANP
khususnya sangat sesuai untuk memodelkan hubungan
interdependensi. Pendekatan ANP didefinisikan sebagai
hubungan jaringan nonlinier antara berbagai faktor.
Melalui metode ANP, akan diprediksi dan dipresentasikan
kompetitor atau cluster (klaster) disertai dengan
dugaan akan adanya interaksi diantara kompetitor-
kompetitor tersebut dan elemen anggotanya termasuk
kekuatan relatif dari interaksi-interaksi tersebut
dalam usaha untuk saling mempengaruhi dalam mengambil
keputusan (Saaty, 2001).
Pada ANP, level-level dalam sistem tidak lagi
lebih tinggi atau lebih rendah, karena sebuah level
dapat mendominasi ataupun didominasi secara langsung
maupun secara tidak langsung oleh level yang lain
sehingga model ANP tidak direpresentasikan dalam bentuk
hierarki, tetapi bentuk jaringan (network).
Dalam membuat keputusan, perlu dibedakan antara
struktur hirarki dan jaringan yang digunakan untuk
mencerminkan bagian-bagiannya. Dalam hirarki level
disusun secara descending menurut pengaruhnya. Pada
jaringan, komponen (sebutan level pada jaringan) tidak
disusun pada urutan tertentu, namun dihubungkan secara
berpasangan dengan garis lurus. Arah panah mencerminkan
pengaruh dari sebuah komponen terhadap komponenyang
lain. Perbandingan berpasangan dalam suatu komponen
dibuat menurut dominasi pengaruh dari setiap pasangan
elemen dalam sistem. Dalam jaringan sistem komponen
dapat dianggap sebagai elemen yang berinteraksi dan
mempengaruhi satu sama lain dengan mengacu pada suatu
kriteria.
Gambar 2.3 Perbedaan antara hierarki linear dengan
bentuk jaringan (Murat & Sucu, 2003)
Hierarki hanya menggambarkan suatu hubungan
ketergantungan fungsional satu arah, yaitu
ketergantungan fungsional (level) bagian bawah terhadap
komponen (level) bagian atas. Jaringan mampu
mengakomodasi ketergantungan fungsional dua arah, yaitu
komponen bagian bawah dan bagian atas saling tergantung
secara fungsional. Namun baik di dalam hierarki maupun
jaringan, elemen-elemen di dalam setiap komponen
diperbolehkan saling bergantung (inner dependent).
2.7.1 Prinsip Pokok Analytical Network Process
Pengambilan keputusan dalam metodologi ANP
didasarkan pada beberapa prinsip pokok, yaitu:
1. Penyusunan jaringan (Network)
Dilakukan oleh pengambil keputusan yang mengetahui
permasalahan secara mendalam. Para ahli harus
mengetahui elemen-elemen yang setara dalam
kualitas ke dalam satu komponen serta mampu
menyatakan apakah terdapat hubungan ketergantungan
atau tidak antarkomponen maupun antarelemen sistem
sendiri.
2. Penentuan bobot elemen terhadap komponen acuan
Dilakukan dengan menggunakan matriks perbandingan
berpasangan seperti pada AHP untuk memperoleh
bobot elemen-elemen dalam suatu komponen terhadap
tiap elemen dalam komponen acuan. Matriks ini juga
dilacak konsistensinya.
2.7.2 Kelebihan Metode ANP
Metode yang selama ini diterapkan menggunakan
beragam pendekatan yang berkisar mulai dari metode-
metode matriks dan penentuan skor sederhana sampai
pendekatanpendekatan pemrograman matematis tingkat
tinggi. ANP ini berada diantara kedua jenis teknik
tersebut, yang tidak membutuhkan kerumitan dari model-
model matematis, tetapi menyediakan suatu solusi yang
lebih kokoh dibanding metode penentuan skor yang
sederhana. ANP secara eksplisit mempertimbangkan antar
hubungan di antara faktor-faktor melalui perbandingan-
perbandingan berpasangan. ANP lebih bagus karena
memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan
pengukuran strategis, operasional, tangible
(kuantitatif) dan intangible (kualitatif) dalam proses
evaluasi (Sarkis; Talluri, 2002).
Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah
kemampuannya untuk membantu dalam melakukan pengukuran
dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau
jaringan. Tidak ada metodologi lain yang mempunyai
fasilitas sintesis seperti metodologi ANP. Sementara
itu, kesederhanaan metodologinya membuat ANP menjadi
metodologi yang lebih umum dan lebih mudah
diaplikasikan untuk studi kualitatif yang beragam,
seperti pengambilan keputusan, forecasting, evaluasi,
mapping, strategizing, alokasi sumber daya, dan lain
sebagainya. ANP juga membebaskan kebutuhan untuk
menyusun komponen dalam bentuk rantai lurus seperti
dalam hirarki. ANP memungkinkan struktur untuk
berkembang lebih alami sehingga merupakan cara yang
lebih baik dalam mendeskripsikan apa yang terjadi di
dunia nyata. Dengan memasukkan dependensi, feedback,
dan siklus pengaruh pada supermatriks, ANP lebih
obyektif dan lebih memungkinkan untuk menangkap apa
yang terjadi pada dunia nyata. Secara keseluruhan ANP
merupakan alat pengambilan keputusan yang baik, namun
memerlukan kerja lebih untuk menangkap fakta dan
interaksi.
2.73 Penyusunan Prioritas
Setiap elemen yang terdapat dalam hirarki harus
diketahui bobot relatifnya satu sama lain. Tujuan
adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan pihak –
pihak yang berkepentingan dalam permasalahan terhadap
kriteria dan struktur hirarki atau sistem secara
keseluruhan. Langkah pertama dilakukan dalam menentukan
prioritas kriteria adalah menyusun perbandingan
berpasangan, yaitu membandingkan dalam bentuk
berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub sistem
hirarki. Perbadingan tersebut kemudian
ditransformasikan dalam bentuk matriks perbandingan
berpasangan untuk analisis numerik. Misalkan terhadap
sub sistem hirarki dengan kriteria C dan sejumlah n
alternatif dibawahnya, Ai sampai An. Perbandingan antar
alternatif untuk sub sistem hirarki itu dapat dibuat
dalam bentuk matris n x n, seperti pada dibawah ini.
Tabel 2.7 Matriks Perbandingan Berpasangan
Nilai adalah a11 nilai perbandingan elemen (baris)
terhadap (kolom) yang menyatakan hubungan :
a. Seberapa jauh tingkat kepentingan (baris) terhadap
kriteria C dibandingkan dengan (kolom) atau
b. Seberapa jauh dominasi (baris) terhadap (kolom) atau
c. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada
(baris) dibandingkan dengan (kolom).
Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh
perbandingan diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai
9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel
berikut ini :
TABEL 2.8 Matriks Perbandingan Berpasangan (Sumber
: Saaty, 1990)
Seorang pengambil keputusan akan memberikan
penilaian, mempersepsikan ataupun memperkirakan
kemungkinan dari suatu hal/peristiwa yang dihadapi.
Penilaian tersebut akan dibentuk kedalam matriks
perbandingan berpasangan pada setiap level hirarki.
Gambar 2.4 Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan pada
Suatu level hirarki
2.7.4 Uji Konsistensi Indeks dan Rasio
Salah satu keutamaan model ANP yang membedakannya
dengan model – model pengambilan keputusan yang lain
adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Dengan
model ANP yang memakai persepsi decision maker sebagai
inputnya maka ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena
manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan
persepsinya secara konsisten terutama kalau harus
membandingkan banyak kriteria. Berdasarkan kondisi ini
maka pengambil keputusan dapat menyatakan persepsinya
tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Pengukuran
konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan
atas eigen value maksimum. Thomas L. Saaty telah
membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks
berordo n dapat diperoleh dengan rumus sebagai
berikut :
CI = Rasio Penyimpangan (deviasi) konsistensi
(consistency indeks)
Lamda max= Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n
n = Orde matriks
Apabila CI bernilai nol, maka matriks pair wise
comparison tersebut konsisten. Batas ketidakkonsistenan
(inconsistency) yang telah ditetapkan oleh Thomas L.
Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi
(CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan
nilai Random Indeks (RI) yang didapatkan dari suatu
eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory yang
kemudian dikembangkan oleh Wharton School. Nilai ini
bergantung pada ordo matriks n. Dengan demikian, Rasio
Konsitensi dapat dirumuskan sebagai berikut :
CR = Rasio Konsistensi
RI = Indeks Random
Bila matriks matriks perbandingan berpasangan (pair-
wise comparison) dengan nilai CR lebih kecil dari 0,100
maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker
masih dapat diterima jika tidak maka penilaian perlu
diulang.
2.8 Strategi Pengembangan (manajemen strategi)
2.8.1 Manajemen Strategi
Manajemen strategis merupakan serangkaian tindakan
yang digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan,
dan mengevaluasi keputusan manajerial dalam mencapai
sasaran perusahaan (Hunger & Wheelen, 2003; Hunger &
Wheelen, 2007). Strategi memiliki keterkaitan yang erat
hubungannya dengan konsep perencanaan dan pengambilan
keputusan, sehingga pada akhirnya strategi bekembang
menjadi manajemen strategi. Proses manajemen strategi
terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya pengamatan
lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi
dan evaluasi strategi (David, 2004; Hunger & Wheelen,
2007).
Tahap pengamatan lingkungan dilakukan untuk
mengidentifikasi berbagai peristiwa, perkembangan dan
perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi
organisasi (Hunger & Wheelen, 2003; Hunger & Wheelen,
2007; Hill & Jones, 2009). Tahap perumusan strategi
adalah tahap pemilihan keputusan dalam pemilihan
alternatif strategi yang akan digunakan oleh
organisasi. Strategi yang dipilih merupakan hasil dari
pengamatan terhadap lingkungan organisasi (Hunger &
Wheelen, 2007; Thompson, 2010).
Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi
strategi, yaitu tahap pelaksanaan strategi yang telah
dirumuskan atau direncanakan. Implementasi strategi
merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi
dan kebijakannya melalui pembangunan program, anggaran
dan prosedur (David, 2004; Harrison & John, 2009).
Tahap terakhir ialah evaluasi dan pengendalian yaitu
melakukan perbandingan hasil yang diperoleh dengan
hasil yang diinginkan untuk memberikan umpan balik yang
diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi dan
mengambil tindakan perbaikan bila diperlakukan (Hunger
& Wheelen, 2007; Kossowski, 2007; Hill & Jones, 2009).
2.9 SOTA (State Of The Art)
SOTA (State of The Art) adalah penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian yang dilakukanuntuk menentukan posisi penelitian yang kita lakukan seperti yang ada pada tabel Tabel XXX berikut:
No Nama Peneliti Judul Masalah yang dibahas Tujuan Metode
1.
Indahsari (2010) Model Penentuan Kompotensi Penentuan kompetensi inti industri daerah Menentukan kompetensi inti surve ke dinas terkait,Inti Industri Daerah bangkalan dan ditentukan oleh macam- industri kreatif daerah scoring data variabel
macam IMKM di berbagai daerah di Bangkalan kabupaten Bangkalan kompetensi inti daerah
2.
Pusparini (2011) Strategi Pengembangan Industri Pemetaan dan strategi pengembangan Mendeskripsikan industri kreatif wawancara, kuisioner, Kreatif Di Sumatera Barat industri kreatif pada subsektor kerajinan subsektor kerajinan, mengidentifikasi(Studi Kasus Industri Kreatif industri bordir/sulaman dan pertenunan rantai nilai industri kreatif subsektor Subsektor Kerajinan) kerajinan, strategi pengembangan,
mengetahui peran cendekiawan, bisnis dan pemerintah.
3.
Pradana (2013) Analisis Potensi Industri Kreatif Pemetaan Industri kreatif berdasarkan Mendeskripsikan pemetaan potensi pemetan industri kreatifSebagai Dasar Penentuan Kompetensi Klasifikasi Buku Lapangan usaha Indonesia industri kreatif dan penentuan berdasar variabel-variabInti Daerah Kabupaten dan menentukan kompetensi inti daerah kompetensi inti Bangkalan Depdag, dan menentukan Bangkalan di kabupaten Bangkalan kompetensi inti daerah
menggunakan metode promethee II
4.
Agustiansyah, Riza (201Penerapan Metode (ANP) Penentuan prioritas perbaikan jalan di Dinas menerapkan metode Analytic Network AHP dan ANPAnalytic Network Process Untuk Pekerjaan Umum, memberikan informasi pada Process (ANP) untuk menentukan Menentukan Prioritas Perbaikan Jalamasyarakat tentang kondisi jalan dan program prioritas perbaikan jalan di Dinas Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor rehabilitasi untuk menanganinya Pekerjaan Umum Kota Bogor
5.
Dewa Ayu, I (2011) Penentuan Skala Prioritas PenanganaPenentuan urutan prioritas penanganan jalan di Menentukan urutan prioritas penanganan AHPJalan Kabupaten Di Kabupaten BangliKabupaten Bangli berdasarkan SK dari Bina berdasarkan SK Dirjen Bina Marga, metode
Marga yaitu SK No. 77/KPTS/Db/1990, AHP, membandingkan hasil urutan prioritas,urutan prioritas dengan AHP, perbandingan prioritamengetahui kelebihan dan kekurangan skalaberdasar SK dan kelebihan kelemahan skala prioritasprioritas penanganan jalan.
6.
Azmi, Alvian (20xx) Perencanaan Strategi Pengembangan Alterntif perancangan strategi yang tepat dengan Mengetahui alternatif perencanaan strategi SWOT dan ANP Industri Rumah tangga Gula Kelapa SWOT dan mengetahui prioritas strategi yang tepat untuk pengembangan usaha gula
pengembangan IRT gula kelapa desa Gledug dengan dengan SWOT, mengetahui prioritas strategi metode ANP pengembangan IRT gula dengan ANP.
7.
Muhimatul, Siti (2013Pemilihan Subsektor Kerajinan UngguMemilih subsektor unggulan pada sektor industri Mendapatkan subsektor kerajinan unggulan Rantai Nilai, AHP dan ANSebagai Dasar Perumusan Strategi kreatif kerajinan dan perumusan strategi pada industri kreatif Bangkalan, Pengembangannya di Kabupaten pengembangnnya mengidentifikasi rantai nilai dan membuatBangkalan rumusan strategi pengembangan serta
menentukan strategi unggulan dengan ANP
DAFTAR PUSTAKA
Agustiansyah, Riza., Ambarsari, Nia. 2012. Penerapan
Metode Analytic Network Process (ANP) Untuk Menentukan Prioritas
Perbaikan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bogor. Fakultas
Rekayasa Industri. Institut Teknologi Telkom.
Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008.
Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025: Rencana
Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015.
Dewa Ayu, I. 2011. Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan
Kabupaten Di Kabupaten Bangli. Thesis. Universitas
Udayana. Denpasar.
Howkinds, John. 2002. The Creative Economy: How People Make
Money from Ideas. Penguin Books. England.
http://www.itelkom.ac.id/ahp/library/1998.
Indahsari, K. 2010. Model Penentuan Kompetensi Inti Industri
Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan). Fakultas Ekonomi
Universitas Trunojoyo: Madura
Sumotarto, U. 2010. Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Alam.
Simposium Nasional Menuju Purworejo Dinamis dan
kreatif. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi
(BPPT), Jakarta.
Pradana, Tegar. 2013. Analisis Potensi Industri Kreatif Sebagai
Dasar Penentuan Kompetensi Inti Daerah Di Kabupaten Bangkalan.
Teknik Industri. Universitas Trunojoyo Madura.
Pusparini, H. 2011. StrategiPengembanganIndustriKreatif di
Sumatra Barat (Studi Kasus Industri Kreatif Subsektor Kerajinan):
Industri Bordir/ Sulaman dan Pertenunan). Perancanaan
Pembangunan Pascasarjana Universitas Andalas:
Padang
Narita, Putri., Ciptomulyo, Udisubakti. 2010. Pemilihan
Prioritas Pengembangan Sektor Industri Kecil Menengah Potensial Di
Kabupaten Bangkalan Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu
Dengan Metode Dhelpi Dan ANP. Teknik Industri. Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.