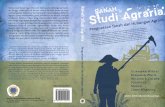Predatory Regime dalam Ranah Lokal : Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo
Transcript of Predatory Regime dalam Ranah Lokal : Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 85
PREDATORY REGIME DALAM RANAH LOKAL: KONFLIK PASIR BESI
DI KABUPATEN KULON PROGO
Predatory Regime in Local Arena: The Con�lict of Iron Ore Mining
in Kulonprogo Regency
Wasisto Raharjo Jati
Peneliti di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
Email: [email protected]
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kon!lik sumber daya alam (pasir besi) yang terdapat di Kulon Progo. Kontestasi kon!lik berpusat pada pengaturan sumber daya alam antara paradigma developmentalisme dan ekologi. Developmentalisme merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tinggi berdasar pada eksploitasi sumber daya alam. Sementara ekologi menghendaki adanya keseimbangan antara manusia dan lingkungan dalam pengaturan sumber daya alam. Adanya temuan pasir besi yang terdapat di Kulon Progo tidak terlepas dari narasi rivalitas tersebut dimana petani melawan koalisi besar antara pemerintah dan korporasi. Hal yang menarik adalah aliansi tersebut dibangun atas dasar patrimonialisme dan feodalisme yang eksis di Yogyakarta.
86
Implikasinya adalah gerakan petani menjadi sempit dan terbatas pada lingkungan mereka saja.
Kata kunci : Kon�lik Pasir Besi, JMI, Kraton, Kon�lik Agraria, Pesisir
Selatan, PPLP
Abstract
This article aims to analyze the power contestation in natural resources (iron ore) con�lict in Kulon progo. This contestation includes ideologies in managing natural resources between the paradigms of developmentalism and ecology. Developmentalism is represented with high economy growth achievement based on natural resources excavation. Meanwhile; ecology is represented with harmony among human and environment in managing natural resources. The exploitation of iron ore in Kulonprogo con�irm the grand narration wherein farmers �ight against alliance of government and corporation. Interestingly, these alliances were built from patrimonialism and feudalism powers that ever exist in Yogyakarta. The implication is, then, social movement from farmers becoming narrow and limited in
their environment.
Keywords: Iron Ore Con�lict, JMI, Sultanate of Yogyakarta, Agrarian
Con�lict, South Coastal, PPLP
PendahuluanI.
Membincangkan masalah kon�lik tata kelola sumber daya alam di
ranah lokal sebenarnya terletak pada bagaimana karakteristik rezim
penguasa tersebut. Hal tersebut terkait dengan perspektif penguasa
dalam melihat potensi sumber daya alam yang berada di wilayahnya.
Perspektif tata kelola sumber daya sendiri sebenarnya dapat
dianalisis dalam dua mahzab yakni perspektif antroposentris dan
perspektif ekologis (Jati,2012). Perspektif pertama mengandaikan
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 87
bahwa sumber daya alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan
manusia sehingga harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Adapun
perspektif kedua melihat dimensi tata kelola sumber daya alam perlu
diseimbangkan karena baik alam maupun manusia sebenarnya saling
membutuhkan satu sama lainnya. Dalam kasus negara berkembang,
manajemen tata kelola sumber daya alam pada umumnya lebih
mengarah pada pemahaman perspektif pertama yakni pola eksploitasi
alam secara maksimal yang kemudian dikonversikan menjadi sumber
pendapatan utama.
Implementasi otonomi daerah yang berlangsung semenjak tahun
1999 sendiri membuat daerah otonomi diharuskan mencari sumber
pendapatannya secara mandiri. Salah satu sumber pendapatan
utama tersebut adalah potensi sumber daya alam yang melimpah.
Hal tersebut mendorong banyak daerah yang kaya sumber daya
alam banyak menerbitkan surat kuasa tambang maupun surat
retribusi pajak sumber daya alam. Pendapatan dari kegiatan tersebut
melimpah ruah, apalagi jika masih ditambah dengan penerbitan
surat kontrak kerja maupun eksplorasi. Kondisi eksploitasi ini
menyimpan paradoksal adanya kerusakan sumber daya alam yang
berada di lingkungan sekitarnya yang semakin rusak parah. Hal
inilah yang menjadi fenomena kutukan sumber daya alam bahwa
kepemilikan sumber daya justru menjadi musibah. Selain itu pula, kue
perekonomian dari hasil ekstrasi sumber daya alam sendiri juga tidak
memiliki trickle-down effect kepada masyarakat karena rembesan
kue tersebut tidak dinikmati masyarakat secara maksimal. Bahkan
banyak terjadi kon!lik sengketa kepemilikan sumber daya alam yang
banyak melibatkan trinitas aktor seperti pemerintah, pengusaha,
maupun masyarakat.
Kon!lik tersebut meliputi pengambilalihan sumber daya alam
berbasis komunal dari rakyat atas nama peningkatan pendapatan
maupun pertumbuhan ekonomi. Maka dalam taraf inilah, rezim
kemudian bertindak secara oligarkis-represif dengan berusaha
mengusahakan kepentingan ekonomi elite ketimbangan kepentingan
ekonomi masyarakat. Implikasi yang timbul adalah sumber ekonomi
88
masyarakat kemudian termajirnalkan atas nama pembangunan
ekonomi tersebut.
Kajian ini mengkaji beberapa pertanyaan penelitian: bagaimana
karakteristik rezim tata kelola sumber daya alam yang berkembang di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga menimbulkan resistensi
dari masyarakat pantai; bagaimana bentuk kon!lik yang terjadi dalam
sengketa pengelolaan sumber daya alam tersebut? Tujuan dari kajian
ini adalah 1) memetakan kon!lik sosial yang terjadi antara masyarakat,
korporasi, dan pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam. 2)
mengetahui bentuk karakteristik resistensi yang dilakukan oleh
masyarakat pesisir Kulonprogo dalam memperjuangkan hak-haknya.
Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai bahan
kontemplasi dalam perumusan kebijakan tata kelola sumber daya
alam yang harus menyinergiskan kepentingan masyarakat. Selain itu
pula, mengetahui implikasi-implikasi sosial-ekonomi lainnya berupa
marjinalisasi ekonomi masyarakat maupun hancurnya ekosistem
dalam masyarakat lokal karena pembangunan ekonomi yang tidak
a!irmatif.
Rezim Tata Kelola Sumber Daya Alam di DaerahII.
Sebelum membahas mengenai karakteristik rezim, terlebih dahulu
kita harus memahami de�inisi mengenai sumber daya alam tersebut.
Adapun yang dimaksudkan dengan sumber daya alam sendiri dapat
digolongkan menjadi dua bentuk yakni �low dan stock (Arizona,
2008). Pertama, sumber daya alam sebagai �low. Pengertian pertama
ini mende�inisikan bahwa sumber daya alam dimaknai sebagai entitas
yang bebas dan dapat diakses secara komunal oleh masyarakat.
Sebagai contohnya adalah hutan, gunung, pesisir pantai, maupun
danau. Selain itu, sumber daya alam sebagai �lows juga dipahami dalam
bentuk faktor produksi atau sebagai barang/komoditas seperti kayu,
rotan, air, tumbuhan, dan ikan yang jumlahnya bisa diperbaharui
kembali dikarenakan karakternya yang dapat bertahan lama dan
terus berproduksi sepanjang lintas generasi. Di samping memegang
fungsi ekstratif, �lows juga memiliki fungsi konservasi seperti hutan
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 89
untuk menampung air dalam tanah dan mencegah degradasi tanah,
mengendalikan kekeringan di musim kemarau, menyerap CO2 yang
ada di udara, mempertahankan kesuburan tanah, maupun mengurai
berbagai bahan beracun limbah industrial. Artinya pemahaman
stock ini mengandaikan bahwa sumber daya berfungsi sebagai
penyeimbang ekosistem maupun pelestarian alam.
Kedua, sumber daya alam dimaknai sebagai stocks. De inisi stocks
sendiri mengindikasikan sumber daya alam dimaknai sebagai sumber
ekonomi yang dapat diekstrasi dan dikomersialisasikan menjadi
komoditas harga tinggi. Sumber daya alam sebagai stocks sendiri
tidak dapat diperbaharui yakni apa yang dimanfaatkan sekarang
tidak dapat dimanfaatkan kemudian hari. Hal inilah yang menjadikan
tingkat utilitas barang tidak seperti �lows yang dapat digunakan
sepanjang masa. Namun demikian karena tingkat komersialisasinya
yang tinggi, maka aksesibilitas masyarakat untuk mengelola stocks
sendiri dibatasi menjadi arena privat yang biasanya dikuasai oleh
korporasi yang memiliki hak izin tambang. Meskipun sudah memiliki
izin tambang, baik �lows maupun stocks sering kali bersinergi dan
bersinggungan satu sama lain. Hal inilah yang menjadi pembatasan
antara komunalisme dan privatisasi menjadi kabur karena sering kali
kepemilikan sumber daya alam menjadi tumpang tindih sehingga
menimbulkan kon lik sosial. Oleh karena itulah, sebenarnya kon lik
tata kelola sumber daya alam biasanya hadir dari wilayah abu-abu
tersebut dan bagaimana konstelasi aktor yang terlibat di dalamnya
terutama dalam tata kelolanya.
Adapun kata kunci dalam memahami rezim tata kelola sumber
daya alam sendiri dapat dipahami melalui pengertian sumber
daya alam sebagai barang (goods) (Fauzi, 2004). Kata goods dapat
diklasi ikasikan dalam berbagai ragam kriteria terentu. Pertama dari
segi konsumsinya, goods sendiri apakah bisa diakses semua orang
ataukah hanya dinikmati orang tertentu (non-rivalry) sehingga tidak
ada kontestasi dalam merebutkan sumber daya alam tersebut karena
hal itu sudah menjadi arena privat. Pemahaman tersebut juga dapat
dipahami sebagai excludable bahwa terdapat upaya “penghalangan”
90
bagi pihak lain untuk ikut menikmati hasil sumber daya alam
tersebut. Maka dari sifat-sifat tersebut, sumber daya alam sebagai
goods sendiri kemudian terbagi dalam dua jenis yakni public goods
dan private goods (Endaryanta, 2008). Adapun public goods sendiri
memiliki sifat seperti rivalry (semua orang bisa mengakses hingga
menimbulkan kontestasi), non-excludable (tidak ada penghalangan
dari pihak tertentu untuk menikmati sumber daya alam), dan non-
divisible (sumber daya alam tersebut tidak pernah habis, meski sering
digunakan). Private goods sendiri merupakan kebalikannya yakni
excludable (penguasaan privat atas sumber daya alam), dan divisible
(sumber daya alam langka dan tidak bisa diperbaharui).
Dikotomi dua jenis barang tersebut membuat dimensi eksternalitas
kemudian menjadi bercabang dua. Dalam public goods, semua orang
mempunyai hak dan memiliki manfaat yang sama baik dari sekto hulu
maupun hilir. Eksternalitas private goods sendiri praktis sangatlah
esklusif berada dalam satu entitas tertentu yang tidak membagi
kemanfaatan (bene�it) dengan masyarakat lainnya. Maka dalam hal
ini, sangatlah urgen dan signi ikan untuk melihat konteks hak (rights)
dalam tata kelola sumber daya alam. Secara garis besar, rezim hak
kepemilikan (property rights regime) dibagi dalam tiga bentuk yakni
states way, market way, dan common pool resources (Ostrom,1990).
Model pertama, Pola negara sentris memiliki keuntungan untuk
membagi secara merata hasil kekayaan sumber daya alam kepada
masyarakat, namun aktor lain tidak diberi peran dalam tata kelola
sumber daya alam karena dimonopoli negara. Model kedua, pola
pasar memberi banyak pilihan konsumtif, namun pasar juga
cenderung ekspansif untuk melakukan komodi ikasi barang publik
menjadi barang privat. Dan yang terakhir Model ketiga, common pool
resources diposisikan sebagai model alternatif dalam pengelolaan
sumber daya alam dimana redistribusi terhadap masyarakat akan
lebih adil dan berkesinambungan.
Konsep hak kepemilikan (property rights) lebih mengarah pada
aktor baik itu negara, pasar, maupun masyarakat. Namun yang ingin
ditekankan di sini adalah bagaimana pola mengelola (managing)
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 91
sumber daya alam tersebut. Hal tersebut berimplikasi dengan
karakteristik rezim dan bagaimana relasi dengan aktor lainnya
sehingga menimbulkan ketimpangan ataukah kesejahteraan. Dalam
hal ini, terdapat dua pola manajemen pengelolaan sumber daya alam
yakni manajemen pengelolaan sumber daya alam tradisional dan
manajemen pengelolaan ekologi politik.
Pertama, kata kunci dalam memahami manajemen tradisional adalah
pembangunan berorientasi pembangunan. Konteks ini merujuk pada
sumber daya alam ini diperlakukan layaknya mesin ekonomi yang
senantiasa dipaksa untuk menghasilkan kemanfaatan manusia.
Vandana Shiva (1995) menilai dimensi pembangunanisme yang
berlangsung di negara dunia ketiga merupakan kelanjutan praktik
kolonialisme yang terjadi di masa lalu. Shiva mengajukan istilah
“sindrom eksploitasi” (exploitation syndrome) untuk mengkritisi
wacana pembangunanisme yang berkembang di negara dunia ketiga.
Sindrom tersebut meliputi dua tahapan utama. Pertama, munculnya
kepemilikan barang privat untuk menggantikan barang publik dalam
manajemen pengelolaan sumber daya alam. Konsep kepemilikan
publik sendiri dinilai tidak menguntungkan dari segi ekonomis dan
tidak mendorong manusia untuk berekspresi secara bebas dalam
beraktivitas ekonomi. Kepemilikan barang privat menciptakan
perilaku konsumtif yang besar untuk memuaskan kebutuhan
ekonomi masing-masing sehingga menciptakan fenomena tragedy
of the commons dalam masyarakat. Kedua, berdirinya aparatus
birokrasi pemerintahan yang melegalkan dan mengizinkan adanya
komersialisasi barang publik tersebut dikarenakan pendapatan
negara amatlah tergantung dari ekstrasi yang dihasilkan dari sumber
daya alam tersebut.
Adanya peralihan sumber daya alam dari barang publik menjadi
barang privat sangatlah erat berkaitan dengan global disorder
maupun global instabilities yang meminimalkan peran negara
dalam aspek ekonomi (Endaryanta, 2008 : 15). Peran eksesif negara
dalam mengatur aktivitas ekonomi dinilai tidak kompetitif dalam
membangun dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat dalam
92
rangka menciptakan angka pertumbuhan ekonomi. Selain eksesif,
negara juga menjalin hubungan harmonis dengan koporasi dan pasar
dalam mengelola sumber daya alam.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pola ketimpangan
hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Bahkan untuk
memperkuat legitimasi dalam mengelola tambang, tidak jarang
kemudian dalam tubuh korporasi sendiri terselip nama-nama
pejabat tinggi sebagai dewan komisaris utama. Maka dalam dunia
sosial politik, pola relasi tersebut acap kali disebut sebagai rezim
politik predator (Evan,1990). Adapun karakteristik dari rezim
predatoris tersebut adalah terjadinya hubungan klientelisme yakni
perselingkuhan bisnis dan politik karena basis ekonomi yang lemah,
penguasaan hasil tambang sumber daya alam yang dikuasai oleh
segelintir elite, dan adanya politik intimidasi terhadap masyarakat
yang mencoba melawan hegemoni dari rezim tersebut.
Manajemen tata kelola sumber daya alam berbasis ekologi. Dalam
pola manajemen ini, Perspektif ekologi-politik hadir sebagai
paradigma alternatif dalam merumuskan manajemen pengelolaan
sumber daya yang a!irmatif dengan kondisi lingkungan alam. Kajian
keilmuan ekologi-politik ini merupakan bentuk perkembangan dari
kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet
bumi, dimana terjadi relasi rumit antara manusia dengan alam yang
saling berkontestasi. Secara de!initif, perspektif ekologi-politik dapat
diartikan sebagai kajian politik yang memahami relasi manusia
dengan perubahan lingkungan sebagai hasil dari proses-proses
politik (Dharmawan, 2007). Oleh karena itulah, kajian ekologi-politik
ini selalu mengkritisi dan mempertanyakan konsep ekonomi-politik
dalam developmentalisme yang berandil besar dalam perubahan
lingkungan. Baik alam dan manusia selama ini berada dalam relasi
oposisi biner dimana manusia yang dianggap sebagai pengatur
sumber daya alam di planet ini selalu bertindak semena-mena
terhadap lingkungan sehingga kemudian menjadi rusak. Adanya
praktik penundukan alam oleh manusia tersebut dalam aliran
etika lingkungan (eco-ethics) disebut antroposentrisme. Secara
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 93
desain ontologis, aliran antroposentrisme ini mengandaikan bahwa
manusia adalah pusat dari seluruh kehidupan dan alam diciptakan
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berperan besar
untuk memberi nilai untuk menentukan layak tidaknya alam sebagai
suatu benda. Oleh karena itulah, manajemen pengelolaan sumber
daya model tradisional bisa dikatakan sebagai tata kelola beraliran
antroposentrisme.
Perspektif ekologi-politik menolak aliran antroposentrisme yang
berkembang dalam wacana pembangunanisme (Jati,2012). Alam
hanya diibaratkan sebagai entitas non-living yang hanya menjadi
objek kuasa bagi manusia. Dalam hal ini, perspektif ekologi politik
sendiri mendorong adanya ekosentrisme. Paradigma ekosentrisme
merupakan aliran dalam etika lingkungan yang memposisikan
antara manusia dengan alam dalam relasi yang timbal balik dan
saling membutuhkan sebagai bagian dari komunitas biosfer. Manusia
dan alam merupakan entitas yang melengkapi dan menghidupi
dalam relasi kausalistik dengan melakukan mekanisme pertukaran
(exchanges).
Dalam membaca kasus kon!lik sumber daya alam dalam ranah lokal,
pembangunanisme berlandaskan manajemen tata kelola sumber
daya tradisional masih menjadi orientasi berpikir utama. Logika
pembangunanisme yang melandaskan pada pertumbuhan ekonomi
yang merembes, namun merembesnya tidak sampai ke bawah adalah
pola umum yang terjadi dalam berbagai kon!lik tersebut. Tidak
banyak daerah di Indonesia yang menerapkan manajemen ekologi
dalam tata kelola karena hal itu sama saja menyia-nyiakan diri
menjadi daerah kaya. Tuntutan untuk menaikkan pendapatan asli
daerah (PAD) merupakan motivasi utama tata kelola sendiri mutlak
menjadi milik negara dan korporasi? Implikasinya yang timbul
kemudian adalah terjadi ketimpangan pendapatan secara struktural
dimana pemerintah bertambah kaya sedangkan masyarakat justru
semakin menderita. Fenomena tersebut seringkali disebut sebagai
kutukan sumber daya alam bahwa hadirnya sumber daya alam
yang sejatinya untuk menghadirkan adanya kesejahteraan, malah
94
justru menghadirkan rivalitas dan penderitaan. Fungsi negara yang
melemah terhadap korporasi dan pasar menimbulkan resistensi dari
masyarakat untuk bangkit melawan ketidakadilan tersebut.
III. Pasir Besi sebagai Public Goods Petani Lahan Pantai
Adapun kasus kon�lik pasir besi di Kabupaten Kulon Progo juga
mengikuti alur narasi dominan tersebut bahwa terdapat potensi
sumber daya alam besar dalam pengelolaan masyarakat yang akan
diakuisisi sepihak oleh pemerintah lokal dan korporasi. Pola akuisisi
sepihak dengan mengandalkan peraturan daerah menimbulkan
gelombang resistensi dari masyarakat. Resistensi tersebut
merupakan upaya masyarakat mempertahankan pasir besi sebagai
kawasan subur pertanian lahan pantai di pesisir selatan Kulon Progo.
Persoalan kemudian berkembang menjadi pelik manakala pemerintah
pun mengeluarkan legitimasi kultural yang mempertegas kuasa
partimonialnya bahwa tanah pesisir di bawah yuridiksi kerajaan.
Kon�lik pasir besi tersebut setidaknya merupakan satu dari sekian
bentuk rezim pembangunanisme lokal yang berkembang pasca
implementasi otonomi daerah.
Lahan pasir pantai selatan Kulon Progo DIY merupakan lahan
yang didominasi oleh tanah pasir. Materi pasir ini diendapkan oleh
aktivitas gelombang laut di sepanjang pantai. Pesisir pantai Kulon
Progo sepanjang garis pantai dengan panjang ± 1.8 km, terbagi dalam
4 kecamatan dan 10 desa yang mempunyai wilayah pantai dengan
kondisi pesisir hampir 100% pasir dengan kedalaman air tanah
antara hingga 12 meter. Lahan pasir ini juga tersebar hingga 2000
meter dari permukaan laut yang diperkirakan luas lahan pasir pantai
daerah Kulon Progo bisa mencapai 3600000 m2, atau sekitar 3600 ha
(Ansori, 2011). Namun dari 3600 ha tersebut, sebanyak 2500 lahan
pantai digunakan untuk pertanian dan perkebunan.
Ditinjau dari historiositasnya, pesisir pantai selatan Kulon Progo
sendiri pada awalnya merupakan kawasan merana yang hanya
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 95
berupa gundukan pasir pantai tak bertuan yang tidak bernilai
ekonomi apapun di kawasan Desa Banaran, Karang Sewu, Bugel,
Pleret, Garongan dan Karangwuni. Namun demikian, pada awal
1980-an salah seorang petani dari dari empat desa tersebut mencoba
berinisiatif menanam produk hortikultura di lahan pasir tersebut.
Kegiatan bercocok tanam di atas lahan pasir berkembang pesat, baik
dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, perkembangan
teknik pengairan dan pemupukan membuat hasil panen cabe, melon
dan semangka yang semakin baik dan banyak. Bersamaan dengan
itu, jumlah masyarakat yang ikut bercocok tanam juga bertambah .
Maka dari situlah kemudian, pemahaman public goods petani mulai
terbentuk karena merasa berhutang budi terhadap pengelolaan
lahan yang merana hingga berkembang menjadi lahan pertanian
subur. Mereka mulai mengadakan komunalisasi hak kepemilikan
tanah setelah tanah tersebut dirasa benar-benar akan bermanfaat
bagi perekonomian mereka.
Kondisi pertanian lahan pasir pantai dimungkinkan menjadi
sumber ekonomi masyarakat unggulan dikarenakan berbagai realita
geomorfologis yang mendukung. Seperti halnya bentang lahan
pertanian yang berupa cekungan di antara dua gumuk pasir, yang dapat
berperan sebagai saluran drainase air irigasi. Kompleks gumuk pasir
secara keseluruhan membentuk relief berombak yang tersusun oleh
material pasir lepas seperti lempun dan debu, yang memungkinkan
sebagai lahan pertanian tanaman semusim, seperti: cabe, tomat,
terong, sawi, atau jenis palawija lainnya. Jenis penggunaan lahan ini
dapat bertahan sepanjang tahun dalam tingkat fertilitas lahannya
dikarenakan ketersediaan air tanah yang cukup, relatif dangkal, dan
rasanya tawar, di seluruh kompleks gumuk pasir dan swale. Adanya
keuntungan gemorfologis tersebut menjadikan proses adaptasi
masyarakat di sekitar pesisir pantai tersebut berkembang menjadi
suatu komunitas petani lahan pasir dengan mendirikan permukiman-
permukiman penduduk. Tumbuhnya permukiman yang semakin
pesat di sekitar wilayah pertanian lahan pantai mengindikasikan
bahwa public goods mengaksentuasi adanya modal sosial di kalangan
masyarakat. Modal sosial tersebut tumbuh seiring dengan semakin
96
meningkatnya migrasi penduduk ke pesisir lahan pantai. Adanya
perasaan senasib untuk mengubah takdir dengan menggarap lahan
pantai adalah cikal bakal terbentuk komunitas petani lahan pantai.
Maka public goods kemudian mengikat mereka secara kolektif baik
spirit dan rohani untuk berkecimpung dalam perekonomian agraris
tersebut.
Secara umum pola sebaran permukiman di daerah permukiman
adalah mengelompok dengan bentuk memanjang sepanjang
pantai, dari timur ke barat. Tingginya ekspektasi terhadap produk
hortikultura dari pertanian pesisir selatan terutama cabai, tomat, dan
sayuran hijau lainnya baik di pasaran lokal maupun provinsi lainnya
menjadikan kawasan pesisir selatan dengan cepat berkembang
menjadi kawasan padat penduduk dengan tingkat densitas tinggi.
Sebagian besar penduduk menggantungkan diri sebagai petani
dan pekerja kebun di sektor perekonomian agraris. Adapun tingkat
densitas tersebut dapat terindikasi dari tabulasi berikut ini.
Tabel 1
Sensus Populasi Petani di Lahan Pantai Kulon Progo
Sumber : (Juhadi, 2010:18)
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 97
Dari Tabel 1 tersebut, kita bisa melihat bahwa konsentrasi petani
lahan pasir sendiri berada di kawasan yang padat seperti desa Karang
Wuni, Garongan, Jangkaran, dan Sindutan. Desa Karang Sewu memiliki
kepadatan lebih dari 300 jiwa per hektar. Padatnya penduduk pada
lahan permukiman di Desa Karang Sewu terutama disebabkan oleh
pola permukimannya yang cenderung mengelompok dan asosiatif
dengan lahan-lahan pertanian. Aktivitas pertanian di desa ini sangat
menonjol sehingga mengontrol pola dan kepadatan permukimannya.
Maka dari pola asosiatif dan soliditas penduduknya inilah yang
kemudian berkembang menjadi suatu paguyuban (gemenschaft)
yang bertujuan mengamankan tanah pertanian pesisir lahan pantai
menjadi identitas budaya sekaligus pula identitas resistensi manakala
negara lokal mulai merangsek merebut tanah tersebut.
Ada empat faktor yang menjadi raison d’etre terbentuknya politik
identitas di kalangan petani lahan pasir. Pertama adalah proses
reintegrasi masyarakat pedesaan dengan penduduk lahan pantai.
Reintegrasi juga berarti reagrarianisasi yang berperan besar
terjadinya ruralisasi pemuda desa yang bekerja di kota untuk kembali
bertani. Implikasi yang muncul adalah bertani kini dipandang sebagai
pekerjaan yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya harga
pangan.
Kedua, Adanya perbaikan kesejahteraan bagi petani lahan pasir.
Adanya sistem komunalisasi pertanian yang dilakukan oleh petani
berimplikasi pada menurunnya tingkat kemiskinan, persediaan
pangan yang bertambah, dan naiknya pendapatan dari setiap
panen raya yang diestimasi mencapai 130 juta rupiah per hektar
dengan asumsi hasil panen sehari mencapai 8-9 ton dengan harga
sekilo Rp 15.000. Begitu berharganya bertani di lahan pasir inilah
yang memunculkan semboyan “bertani atau mati” sebagai bentuk
penegasan atas penolakan tambang pasir besi.
Ketiga, adanya kebangggan bagi kelompok petani sebagai pionir
dalam pertanian lahan pasir yang pertama di Indonesia yang pertama
dilakukan di Kulonprogo. Maka, konteks kesuburan dan produktivitas
98
tanah pasir besi menjadi narasi penting dalam pembentukan identitas
tersebut (Yanuardy,2012).
Keempat, Mutualisme ekonomi antara sektor agraris dengan
geomorfologis tersebut pada akhirnya menghasilkan keuntungan
yang maksimal. Dari hasil pertanian bawang merah, petani akan
mendapatkan penghasilan Rp53.085.977,48 untuk setiap hektarnya.
Sementara untuk usaha tani komuditas cabai, petani memperoleh
penghasilan sebesar Rp 8.668.116,68 untuk setiap hektarnya. Secara
keseluruhan, produksi pertanian di 1 hektar lahan pasir bisa memberi
keuntungan bersih sebesar lebih dari Rp 30 juta dalam setahun. Hal
ini tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan apabila hanya menanam
padi pada 1 hektar sawah yang hanya memberi keuntungan maksimal
Rp 4 juta setahun. Maka tidaklah mengherankan, apabila petani
pesisir lahan pantai berusaha mati-matian untuk mempertahankan
tanah pertanian terhadap upaya eskavasi lahan pantai pesisir selatan
Kulon Progo oleh PT Jogja Magasa Mining selaku investor.
IV. PT Jogja Magasa Mining dan Kon�lik Pasir Besi
Potensi pasir besi di pesisir selatan Kulonprogo mulai tercium pada
tahun 2003. Hal itu diindikasi dari temuan kajian geologi yang
menyebutkan bahwa kandungan pasir besi di Kulonprogo sendiri
mencapai 300 juta ton kubik dengan prosentase produktivitas
mencapai 500.000 hingga 2 juta ton per hari (Ansori,2011:90). Potensi
pasir besi yang luar biasa ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik
mineral magnetik yang terdapat di dalam pasir besi. Adanya variasi
mineral magnetik di dalam pasir besi memungkinkan munculnya
pilihan alternatif dalam pemanfaatan pasir besi yang lebih komersial.
Adapun pilihan alternatif tersebut adalah kandungan vanadium yang
berharga di dalam perut pasir Kulonprogo. Dengan demikian, pasir
besi di pesisir selatan wilayah Kulon Progo tersebut dapat dikatakan
emas hitam, karena harganya bisa seribu kali lipat dibanding besi
biasa.
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 99
Besarnya potensi yang dimiliki pasir besi Kulonprogo inilah yang
kemudian menarik pemerintah dan investor untuk melakukan
kegiatan eskavasi pertambangan di daerah tersebut dengan
membentuk perusahaan patungan bernama PT Jogja Magasa
Mining. Dari hasil eskavasi tersebut diharapkan, pasir besi dapat
mensejahterakan penduduk DIY khususnya Kulonprogo yang selama
ini dicap sebagai kabupaten tertinggal bersama Kabupaten Gunung
Kidul dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional
provinsi. Namun pada saat yang sama, rencana pertambangan tersebut
ditolak oleh para petani pesisir selatan karena penambangan pasir
besi sampai kedalaman 14,5 meter, dengan bentang atau sepanjang
22 kilometer, serta lebar 1,8 kilometer akan mengakibatkan abrasi
laut dan mengancam pertanian. Meskipun dinilai menguntungkan
secara ekonomi, bene!it yang dihasilkan tidak akan bertahan lama
hanya mencapai 30 tahun masa aktif, selebihnya akan berdampak
destruktif luar biasa terhadap ekosistem pertanian.. Sebaliknya,
pemerintah tetap bersikukuh bahwa pertambangan ini tidak
menganggu pertanian masyarakat karena letaknya yang jauh dari
aktivitas eskavasi.
Adanya tarik ulur kepentingan itulah yang kemudian berkembang
menjadi kon!lik pasir besi antara pemerintah provinsi, korporasi,
dan masyarakat. Dimensi lokus kon!lik juga berkembang selain
pasir kini juga merambah pada masalah agraria. Oleh karena itulah,
membaca pemetaan kon!lik Kulonprogo sebenarnya bersumber
pada dua hal: kon!lik pasir besi dan kon!lik agraria. Kon!lik pasir besi
sendiri terkait dengan kontestasi perebutan mineral pasir besi antara
penambang dan petani sebagai pertanian ataukah eskavasi. Kon!lik
agraria adalah kon!lik pemerintah dan masyarakat yang menuding
tanah di pesisir selatan Kulonprogo adalah milik pemerintah, namun
di sisi sebaliknya petani mengklaim bahwa tanah pesisir merupakan
hak mereka. Adanya hubungan segitiga inilah yang menjadikan
permasalahan kon!lik belum selesai sampai detik ini. Relasi kon!lik
pasir besi tersebut bisa dideskripsikan melalui gambar berikut ini.
100
Gambar 1. Pemetaan Kon�lik Pasir Besi
Dalam Gambar 1 tersebut dideskripsikan bahwa potensi kon�lik
sendiri berkembang dalam tiga kaki yakni pemerintah, korporasi,
dan masyarakat. Namun demikian, tampak bahwa negara dan
korporasi telah berkongsi satu sama lainnya sehingga melemahkan
posisi masyarakat dalam pola manajemen kon�lik tersebut. Di satu
sisi lainnya, masyarakat tidak berdaya menghadapi dua monster
titan pembangunanisme tersebut dimana pola interaksi terhadap
keduanya tidak terjalin bahkan terputus.
Munculnya PT Jogja Magasa Mining yang kemudian bertransformasi
menjadi PT Jogja Magasa Iron pada 2008 menarik untuk dicermati
(JMI,2012). Korporasi yang didirikan oleh para kerabat Keraton
ini seperti halnya GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun, dan BRMH
Hario Seno secara jelas memiliki kepentingan besar terhadap pasir
besi tersebut guna semakin memperkaya diri kalangan elit Kraton
dan. Munculnya PT JMI sebagai bagian dari bisnis kerajaan tersebut
memang tidak terlepas dari dicabutnya kedaulatan ekonomi dan
politik kerajaan untuk diserahkan kepada pemerintah nasional.
Posisi Sultan dan Pakualam yang memihak kepada PT JMI ini
secara jelas semakin mempersulit petani pesisir Kulonprogo untuk
mengadvokasi di tingkat lokal. Masyarakat awam secara jelas juga
lebih memihak Sultan dan PT JMI tanpa pernah mengetahui adanya
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 101
perlawanan dari petani Kulonprogo terhadap aktivitas pertambangan
tersebut yang dianggap dapat merugikan pertanian mereka. Apalagi,
dengan stigmatisasi bagi yang melawan Kraton akan dianggap
sebagai aktor non-keistimewaan oleh masyarakat luas. Maka tidak
jarang, terdapat pola intimidasi oleh sekelompok orang pro Kraton
dan Pakualaman terhadap kelompok petani lahan pantai tersebut.
Selain masyarakat dan pemerintah yang sudah mendiskreditkan
perjuangan petani, suara mereka juga kurang terdengar di parlemen
lokal karena semuanya memihak pada pemerintahan provinsi.
Implikasinya, ada proses pembiaran dalam konteks pemerintahan
lokal terhadap kon!lik lahan pasir yang sudah berlarut-larut dina!ikan
demi menjaga eksistensi keistimewaan. Masyarakat petani pesisir
lahan pantai Kulonprogo justru tidak menikmati keistimewaan
tersebut karena yang memperoleh status istimewa justru elite
kerajaan, pemerintahan, beserta loyalisnya sendiri. Keistimewaan
justru dimanfaatkan oleh elite kerajaan untuk mengklaim tanah-
tanah yang statusnya abu-abu untuk diklaim sepihak. Sikap
dominatif pemerintahan dalam memainkan diskursus keistimewaan
tersebutmembungkam segala bentuk perlawanan petani tersebut.
Hal inilah yang menjadikan perlawanan petani lahan pantai hanya
terlokalisasi di seputaran kawasan pesisir pantai (Ratnawati,2012).
Meskipun pada akhirnya perjuangan para petani ini kemudian
diapresiasi dalam forum NGO internasional di Manila pada 2013 dan
bahwa jejaring NGO di bidang penyelamatan lingkungan sendiri siap
untuk melakukan aksi advokasi di dunia internasional.
Kon!lik pasir besi Kulonprogo memperlihatkan adanya kontestasi
ideologi antara perjuangan ekosistem alam yakni dengan mengelola
alam berbasis paradigma ekologi politik dan juga perjuangan
dalam menaikkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi pertambangan pasir besi berdasar logika
pembangunanisme. Dari segi ekologi-politik, keberadaan PT JMI
dalam melakukan kegiatan eskavasi pertambangan memang sangat
riskan mengingat kondisi geomorfologis yang sebenarnya tidak
mendukung hadirnya tambang disana. Hal ini dikarenakan, Pertama,
102
kawasan pesisir selatan masuk ke dalam kawasan rawan gempa
dan tsunami karena posisinya yang terletak di pertemuan patahan
benua Asia dan Australia di kawasan laut selatan. Kedua, hancurnya
ekosistem gumuk pasir yang diklaim sebagai satu dari tiga ekosistem
pantai terunik di dunia. Gumuk pasir bergerak Kulon Progo merupakan
jalur melintasnya burung-burung migran yang biasa digunakan oleh
para ornitologis untuk mengamati pola migrasi burung dari utara ke
selatan dan sebaliknya. Setidaknya dua pemahaman besar tersebut
mewarnai kontestasi kon lik pasir besi Kulonprogo yang dapat
diringkas dalam tabulasi berikut ini.
Tabel 2
Kontestasi Ideologi dalam Kon�lik Pasir Besi Kulonprogo
Indikator Pembangunanisme Ekologisme
Eksistensi
Pasir Besi
Pasir besi dipandang secara subor-
dinatif sebagai mesin pertumbuhan
ekonomi
Pasir besi dipandang secara
a irmatif bahwa terjadi
hubungan depedensi antara
manusia dan alam
Kesejahteraan
Penduduk
Paham trickle down effect, Royalti
dari pertambangan sebanyak 4,95
triliun rupiah akan diredistribusi-
kan sebanyak 400 milyar per desa
untuk meningkatkan kesejahte-raan
lokal melalui skema CSR (Corporate
Social Responsibility)
Pasir besi merupakan pon-
dasi ekonomi agraris yang
berkelanjutan tanpa merusak
alam. Potensi pertanian lahan
pasir sendiri mencapai 100-
200 juta rupiah tiap musim
panen tiba
Pembangunan
Lingkungan
Pembangunan mengikuti AMDAL,
setelah masa izin usaha selesai da-
lam 30 tahun akan dilakukan proses
remediasi lingkungan
Dalam berbagai kasus, per-
tambangan selalu mening-
galkan dampak destruktif,
pertanian sendiri menjadi
solusi dalam menjaga kon-
servasi air dan gumuk pasir
sebagai biota
Pola dan sifat
pengelolaan
pasir besi
Pengelolaan pasir besi dilakukan
scara tertutup karena mengandal-
kan padat modal
Pengelolaan dilakukan secara
terbuka berbasis komunitas
berbasis padat karya
Penguasaan
Pasir Besi
Penguasaan dilakukan secara
hierarkis struktural tanpa pelibatan
masyarakat
Penguasaan dilakukan secara
komunal oleh masyarakat
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 103
Dari Tabel 2, kita bisa menyimpulkan bahwa rivalitas kedua
ideologi tersebut mencerminkan adanya arogansi kekuasaan
melawan kepentingan komunal. Arogansi tersebut salah satunya
termanifestasikan melalui adanya penyimpangan aturan-aturan
tentang lingkungan hidup demi memuluskan jalan proyek tersebut.
Berbagai aturan tersebut ada pula yang saling terdistorsi satu
sama lain seperti halnya ada penyimpangan-penyimpangan dalam
Perda No. 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi DIY. Dalam pasal 59 huruf c disebutkan bahwa
pengembangan kawasan dengan potensi sumber daya mineral,
batu bara dan panas bumi secara optimal dengan memperhatikan
daya dukung lingkungan. Namun kemudian aturan tersebut justru
bertentangan dengan pasal 60 ayat 2 poin b nomor 2 dengan
ditetapkannya kecamatan Wates, Panjatan, dan Galur sebagai area
penambangan pasir besi. Padahal kajian tematik sebelumnya telah
mengingatkan adanya ancaman tsunami dan abrasi akut bilamana
aktivitas pertambangan tetap dilakukan. Dalam aturan lainnya, Kuasa
Pertambangan No. 008/KPTS/KP/EKPL/X/2005 meliputi lahan
Pakualaman dengan luas area pertambangan 4.076,7 hektar yang
kemudian direvisi menjadi 2.987,79 Ha, yang terletak di sepanjang
pantai antara Sungai Progo dan Sungai Serang (Amri, 2008:28).
Semakin besar area pertambangan justru akan semakin mengancam
keberadaan pertanian lokal sehingga secara gradual akan mematikan
pendapatan masyarakat petani secara struktural. Oleh karena itulah,
penting untuk disimak mengenai dimensi-dimensi lokus kon�lik yang
berkembang dalam kasus Kulonprogo agar bisa diketahui duduk
perkaranya.
V. Kon�lik Pasir Besi sebagai Permasalahan Sengketa Agraria
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kon�lik sumber daya
alam yang terjadi dalam kasus Kulonprogo merupakan embrioisasi
dari dua model kon�lik yakni kon�lik agraria dan kon�lik pasir besi.
Adapun kon�lik pasir besi tersebut merupakan arena kontestasi
antara petani dan korporasi dalam memperebutkan kandungan pasir
besi demi kelangsungan kegiatan perekonomian mereka. Kondisi
104
keberkahan itulah yang menjadi keunikan tersendiri dalam kasus
pertanian Indonesia dimana produk varietas unggulan hortikultura
justru dihasilkan di kawasan yang selama ini dilabelisasi tandus.
Apalagi ditambah dengan margin keuntungan yang bisa mencapai
10-20 juta per bulan untuk 1200 hektar lahan yang ditanami produk
hortikultura (Panuju,2013). Selain itu pula, pertambangan pasir
besi tersebut akan memiliki dampak terhadapnaiknya air laut ke
permukaan pantai sehingga mengakibatkan abrasi dan hilangnya
air tawar karena kadar garam laut mencemari air daratan. Realitas
tersebut yang kemudian membuat daya survivalitas dan durabilitas
petani semakin meningkat untuk tetap menjaga dan mempertahankan
keberadaan pasir besi sebagai aset pertanian berharga.
Berbeda halnya dengan pemahaman petani terhadap pasir besi yang
sebatas pada kandungan alluvium yang berguna bagi pertanian, PT
Jogja Magasa Iron sendiri menangkap adanya kandungan titanium
dan vanadium berharga sebanyak 300 juta ton di pesisir selatan
yang dapat dieskavasi selama 30 tahun masa aktif. Tentu hal tersebut
menjadi keuntungan regional bagi DIY yang memiliki Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terendah se-Jawa untuk meningkatkan kas
daerah melalui skema kontrak karya dan bagi hasil tambang. Hal
yang menjadi lokus permasalahan adalah penambangan tersebut
dikhawatirkan akan juga ikut menggerus kandungan alluvium
yang ternyata memiliki konsentrat yang sama dengan titanium dan
vanadium yang diincar korporasi (Syaifullah, 2011). Indikasinya
bisa disimak dari perluasan lahan pertambangan yang semula hanya
pilot project di kawasan Galur kemudian berkembang ke empat
desa, salah satunya adalah Karangwuni sebagai sentral permukiman
petani pantai selatan. Selain itu pula, pertambangan juga diperluas
mendekati DAS Sungai Progo dan Sungai Serang yang merupakan
pusat kandungan alluvium dan konservoir air tawar bagi pertanian.
Adanya ekstensi!ikasi pertambangan pasir besi inilah yang membuat
resistensi petani juga semakin meningkat. Para petani tidak rela jika
kandungan alluvium dan air tawar itu dirusak oleh mesin-mesin
eskvator dan deru haul truck bergemuruh di lingkungan mereka
sehingga mematikan sumber pendapatan mereka selama ini.
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 105
Berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah menetpakan kawasan
pesisir selatan ditetapkan sebagai area pertambangan pasir besi
sejak 2003. Penetapan tersebut memang dirasa dilakukan sepihak
oleh pemerintah pusat beserta provinsi tanpa melibatkan upaya
konsultasi petani sebagai aktor in situ di sekitar pertambangan.
Penetapan itu pula yang kemudian turut mengubah rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten kulonprogo yang semula menetapkan
kawasan pesisir selatan sebagai kawasan hijau menjadi kawasan
tambang. Dalam lingkup nasional, skema Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I) yang disusun pada tahun
2012 guna mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
kawasan tertinggal seperti halnya Kulonprogo, mengamanatkan
adanya eksploitasi tambang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi
yang kemudian akan memicu pertumbuhan infrastruktur ekonomi
Kulonprogo. Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) sendiri
dibentuk pada tahun 2006 sebagai bentuk akumulasi gerakan petani
di pesisir selatan yang kecewa dengan sikap pemerintah pusat dan
daerah. Gaung PPLP dalam mengadvokasi perjuangan hak-hak petani
di tingkat lokal harus diakui minim selain dikarenakan dominasi
paternalistik dalam tubuh pemerintahan yang pro terhadap kerajaan
sehingga membatasi gerakan petani. Jejaring paternalistik rupanya
juga membungkam segala pemberitaan media yang membahas arah
perjuangan petani tersebut. Yang paling menyakitkan adalah PPLP
justu dianggap sebagai organisasi anti keistimewaan yang mencoba
melawan Sultan dengan menduduki tanah-tanah pesisir selatan.
Konstruksi tersebut menjadi bagian penting untuk membungkam
perjuangan PPLP di tingkat lokal sehingga organisasi ini mengarahkan
orientasi gerakan ke dunia internasional.
Permasalahan sengketa agraria merupakan narasi yang urgen dan
signi!ikan dalam membahas akar permasalahan kon!lik pasir besi
dari segi perspektif alternatif. Perebutan potensi pasir besi memang
menjadi bahasan utama, namun kon!lik agraria merupakan kon!lik
laten yang ternyata menjadi faktor di belakang layar yang berperan
penting terhadap bibit-bibit kon!lik pasir besi.
106
Hal yang paling kentara dalam melihat kon�lik agraria di pesisir
selatan Kulonprogo sebenarnya adalah kontestasi antara penerapan
Undang-undang (UU) PP Agraria tahun 1960 dengan sistem Pakualam
Ground (PG) maupun Sultan (SG) yang berlaku di Yogyakarta.
Keinginan petani sebenarnya adalah melakukan serti�ikasi tanah atas
lahan pertanian mereka yang telah dikelola selama 20 tahun sampai
sekarang ini. Serti�ikasi tersebut sangatlah urgen dan signi�ikan
untuk memperjelas status tanah agar tidak salingklaim mengklaim
tanah pertanian dengan pihak kraton. Dalam hal ini, sudah menjadi
rahasia umum apabila status tanah di kawasan pesisir selatan yang
menjadi sumber sengketa pasir besi masih berstatus abu-abu baik
dari segi hak kepemilikan (property rights) maupun legalitasnya
(ground legality).
Dari segi kepemilikan, terjadi sengketa apakah tanah tersebut milik
petani atau milik Pakualam (Pakualam Ground). Sedangkan dimensi
legalitas juga mempertentangkan berlaku atau tidaknya UU Pokok
Agraria di DIY. Kasus ini menjadi unik dalam peta politik agraria
dalam ranah lokal dimana terjadi dualisme dalam pengaturan tanah.
Masing-masing pihak saling melakukan aksi pembenaran bahwa
tanah yang duduki adalah sah dan mempunyai hak kepemilikan
yang diatur undang-undang. Pihak kraton sendiri bersikukuh
diterapkannya UU No 13 tahun 2012 khususnya pasal 7 dan pasal
32 tentang tanah sebagai bagian dari keistimewaan. Sedangkan
pihak petani menginginkan agar UU No 5 tahun 1960 tentang
Agraria diberlakukan di DIY agar terjadi proses redistribusi lahan
yang merata bagi rakyat. Berlaku tidaknya peraturan tersebut perlu
dilacak dari segi sejarah sehingga kita bisa mengindikasikan berbagai
permasalahan elementernya
Rasionalitas petani lahan pasir menuntut serti�ikasi bisa disimak dari
perjuangan mereka sebagai kaum marjinal yang menjadikan tanah
pantai sebagai sumber pengharapan ekonomi baru. Masyarakat
petani lahan pantai yang berada di pesisir selatan Kulonprogo pada
dasarnya merupakan kelompok masyarakat tanpa tanah (landless)
dan miskin ketika pemerintah kolonial menarik ½ Ha maupun ¼ Ha
untuk ditanami gula. Pada era paska kolonial, kemiskinan rupanya
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 107
juga tidak beranjak dari masyarakat tersebut ketika pengaturan tanah
dalam sistem feodalisme diberlakukan keraton dengan mengklaim
tanah tak bertuan menjadi milik kerajaan. Oleh karena itulah, mereka
kemudian beralih ke pesisir selatan yang kemudian dikenal dengan
sebutan wong Cubung. Kata cubung sendiri mengindikasikan bahwa
kelompok masyarakat tersebut merupakan kelompok orang yang
terbuang dan diibaratkan sebagai kasta sudra jikalau dianalogikan
dengan sistem kastanisasi. Lambat laun, lahan pantai tersebut
kemudian digarap dengan dua sistem yakni tanah pemajekan yakni
tanah yang diklaim legal dan sah untuk dijadikan sebagai lahan
permukiman dan tanah pasir garapan yang digunakan sebagai lahan
pertanian. Mekanisme endog-endogan sendiri digunakan sebagai
forum petani untuk mendiseminasikan pengetahuan pertanian
maupun redistribusi kesejahteraan agar semua petani lahan pasir
menjadi sejahtera.
Maka dengan melihat alasan historis tersebut, serti!ikasi atas
tanah menjadi harga mati bagi para petani. Apalagi hal tersebut
diperkuat oleh UU 5/1960 tentang Pokok Agraria dimana setiap
tanah tak bertuan yang sudah diduduki selama 20 tahun lebih, maka
dimungkinkan untuk dilakukan serti!ikasi hak milik (Yuliandry,
2012:4). Adapun dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954, di
mana pasal 10 mengatakan bahwa orang yang memakai tanah secara
turun-temurun, (tanah itu) bisa dijadikan hak milik. Adanya legalisasi
itulah yang kemudian membuat masyarakat petani lahan pantai
untuk menolak tambang pasir dan dilakukan serti!ikasi dikarenakan
dari seluas 3000 hektar tanah yang hendak dijadikan area tambang,
hanya 200 hektar saja yang berstatus Pakualaman Ground (PG).
Klaim petani tersebut didasarkan pada inventarisasi peta desa yang
menggambarkan pola batas-batas yang jelas.
Sementara itu di lain pihak, pihak kerajaan sepertinya juga ingin
tetap mempertahankan status tanah “tak bertuan” tersebut. Kraton
melalui perundangan Riksjblaad Kesultanan 1918 yang mengatakan
bahwa semua tanah yang tidak terserti!ikasi otomatis menjadi milik
kerajaan. Adapun tanah yang berada di pesisir selatan berdasarkan
pada UU No 18 Tahun 1951 sendiri tentang pembentukan gabungan
108
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Adikarta menyebutkan bahwa
keseluruhan wilayah Adikarta yang meliputi pesisir selatan secara
otomatis berada dalam kekuasaan kraton (Munsyarif, 2010). Adanya
fakta historis yang tidak kalah kuatinilah yang membuat pemerintah
daerah juga berkeinginan besar untuk tetap mempertahankan wilayah
ini. Apalagi setelah UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Yogyakarta diundangkan yang memaknai pengaturan tanah menjadi
bagi dari keistimewaan kraton sebagai patron Yogyakarta. Adanya
silang pendapat terhadap legalitas tambang maupun tanah pertanian
itulah, hingga kini kon lik tersebut belum selesai. Pertanian lahan
pasir masih berjalan seperti biasanya, namun kegiatan pertambangan
sendiri mengalami hambatan karena blokade masyarakat lokal.
Sangatlah penting untuk disimak mengenai diskursus keistimewaan
sendiri dalam memaknai kon lik sumber daya alam di Kulonprogo.
Dalam berbagai hal, keistimewaan sendiri dimaknai sebagai bentuk
pengakuan atas kesetiaan dan pengabdian yang dilakukan Kraton
Yogyakarta dan Pakualaman terhadap perjuangan eksistensi NKRI
selama revolusi kemerdekaan maupun pengakuan entitas lokal
pertama terhadap pemerintah pusat yang baru tumbuh. Namun
keistimewaan juga dapat diartikan sebagai semakin berkuasanya
Kraton terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta.
Maka tidaklah mengherankan bahwa loyalitas rakyat terhadap
kraton begitu tinggi seiring dengan semakin tingginya pula saluran
patrimonialisme tersebut.
Masyarakat pesisir selatan Kulonprogo adalah anomali dalam
rancang bangun patrimonialisme yang berani melawan otoritas
kerajaan yang notabene dianggap populis oleh mayoritas penduduk
lainnya. Namun demikian, semboyan bertani atau mati sendiri
merupakan bentuk penegasan bahwa penguasa sendiri juga harus
mawas diri untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyatnya yang
selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari mengolah tanah
ketimbang mengikuti logika asing demi menjaga pertumbuhan dan
peningkatan pendapatan lokal.
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 109
VI. Kesimpulan
Hal yang bisa kita simpulkan dari makalah ini adalah kon!lik sumber
daya alam yang terjadi dalam ranah lokal selalu saja mempertautkan
kontestasi pembangunanisme dan ekologisme. Dalam kasus kon!lik
pasir besi di Kulonprogo, setting kon!lik tersebut mengikuti alur narasi
besar tersebut. Namun yang menarik dalam kasus kon!lik pasir besi
ini adalah munculnya neo-kapitalisme semu dan patrimonialsime
bisnis yang cukup kuat. Adanya kerajaan di Yogyakarta yang diakui
dan sangat dihormati sebagai patron oleh mayoritas masyarakat
menjadikan gerak advokasi dan pergerakan aktivisme yang menuntut
keadilan agraria menjadi minor pengaruhnya. Sebagai implikasinya
adalah gerakan petani justru terbatas dan terlokalisasi dalam
kawasan lingkungannya saja. Meskipun kini sudah ada berbagai
dukungan internasional terhadap perjuangan tersebut, namun
belum memberi pengaruh besar terhadap gerakan petani tersebut.
Adanya sistem tumpang tindih dalam pengaturan tanah di Yogyakarta
juga menyebabkan gerakan petani mengalami kendala mengenai
property rights. Kon!lik sumber daya baik pasir besi maupun agraria
Kulonprogo menuntun kita pada suatu pemahaman bahwa predatory
regime dalam tata kelola sumber daya timbul karena adanya hasrat
pembangunan yang begitu kuat dengan dukungan modal asing
sebagai stimulusnya.
-oooOooo-
Daftar Pustaka
Ansori, Chusni.(2011). Distribusi Mineralogi Pasir Besi pada Jalur
Pantai Selatan. Buletin Sumber Daya Geologi, 6(2), 81- 96.
Arizona,Yance.(2008).Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam.
Jakarta: Penebir HuMa.
110
Cahyono,Heru. (2011, Maret 31). Menambang Pasir Besi di Lahan
Petani Kulon Progo. Antaranews.com. Retrieved Mei 7,
2013, from http://www.antaranews.com/berita/252134/
menambang-pasir-besi-di-lahan-petani-kulon-progo.
Dharmawan, A. H. (2007). Kon�lik Sosial dan Resolusi Kon�lik: Analisis
Sosio-Budaya. paper presented at Seminar dan Lokakarya
Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan
Kalimantan, (hal. 1-14). Pontianak 10-11 Januari.
Endaryanta. Erwin.(2008).Politik Air: Penjarahan Si Gedang oleh
Korporasi Aqua-Danone. Yogyakarta: PolGov.
Evan, Peter. (1990). Predatory, developmental, and other apparatuses:
A comparative political economy perspective on the Third
World state. Sociological Forum, 4(4), 561-587.
Fauzi, Akhmad.(2004). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jati, Wasisto Raharjo. (2012). Manajemen Tata Kelola Sumber Daya
Alam Berbasis Paradigma Ekologi-Politik. Jurnal Politika, 3(2),
98-111.
JMI. (2012). Sejarah Perusahaan.jmi.co.id. Retrieved Mei 4, 2013, from
http://jmi.co.id/id/his.html.
Juhadi. (2010). Analisis Spasial Teknologi Pemanfaatan Lahan
Pertanian Berbasis SIG di DAS Hulu, Kulonprogo, Yogyakarta.
Jurnal Geogra i, 7(1), 11-29.
Marwasta, Djaka. (2007). Analisis Karakteristik Permukiman Desa-
desa Pesisir di Kabupaten Kulonprogo. Forum Geogra i, 21(1),
57-68.
Munsyarif. (2010). Kebijakan Pengaturan Pertanahan di DIY. paper
presented at Focus Group Discution Pusat Penelitian dan
Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, (hal.1-23)/
Jakarta 23 Desember.
Ostrom, Ellinor. (1990). Governing the Commons: The Evolution of
Institutions for Collective Action. London :Cambridge University
Press.
Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 The Habibie Center 111
Panuju, Triangga. (2013, Mei 29). Tiap Hari Rp 4 Miliar Mengalir
ke Petani Cabai Pesisir. suaramerdeka.com. retrieved Juli 13,
2013, from http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/
news/2013/05/29/158846.
Ratnawati, Tri. (2011). Antara “Otonomi” Sultan dan “Kepatuhan”
Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Governance, 2(1), 42-68.
Shiva,Vandana.(1995). Biopolitics: A Feminist and Ecological Reader
in Biotechnology. London: Zed Books.
Yanuardy, Dian. (2012). Commoning, Dispossession Projects and
Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining
in Yogyakarta. paper presented at International Conference on
Global Land Grabbing II, (hal.1-27). Ithaca 17-19 Oktober.