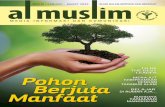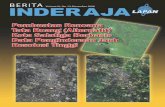Pimpinan Redaksi - jurnal untad - Universitas Tadulako
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pimpinan Redaksi - jurnal untad - Universitas Tadulako
Editorial
Pimpinan Redaksi Dr. Muhammad Khairil, S.Ag., M.Si, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako,
Indonesia
Editor
Dr. Ani Susanti, S.I.Kom, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Dr.Hj. Andi Mascunra Amir, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Dr. Christian Ttndjabante, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Dr. Intan Kurnia, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Section Editor Gemilang Bayu Ragil Saputra, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako
Bohari Bohari, Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Tadulako University, Indonesia
TABLE OF CONTENTS
INFLUENCE OF ADDITIONAL EMPLOYMENT INCOME (TPP) ON IMPROVING
COMPETENCY, PERFORMANCE AND DISCIPLINE OF PUBLIC SERVANT
PENGARUH PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI, KINERJA DAN DISIPLIN PNS
PROVINSI SULTENG
DERRY B. DJANGGOLA .............................................................................................................. 1
POLICY OF TERITORIAL AND REGIONAL REGULATION OPPORTUNITIES IN
CENTRAL SULAWESI
KEBIJAKAN REFORMASI TERITORIAL DAN PELUANG PEMEKARAN DAERAH DI
SULAWESI TENGAH
RIZALI DJAELANGKARA ........................................................................................................ 10
THE OPINION OF COMMUNICATION SCIENCE STUDENTS ON CYBERSTALKING
PHENOMENON IN SOCIAL MEDIA
OPINI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI TERHADAP FENOMENA
CYBERSTALKING DI MEDIA SOSIAL
MUHAMAD ISA YUSAPUTRA, DYAH FITRIA KARTIKA SARI, ROMAN R. UTAMA,
ALDINA HUSNUZAN ............................................................................................................... 24
THE ROLE OF THE PALU CITY PUBLIC RELATION OFFICERS IN THE FESTIVAL PALU
NOMONI IN MAINTAINING IMAGE OF PALU CITY
PERANAN HUMAS PEMDA KOTA PALU PADA EVENT FESTIVAL PESONA PALU
NOMONI DALAM MENJAGA CITRA KOTA PALU
ALDIMAS D. SAMPOERNO ...................................................................................................... 34
COMMUNICATION CLIMATE ON PALU TRASHBAG COMMUNITY
IKLIM KOMUNIKASI PADA KOMUNITAS TRASHBAG PALU
DWI DESRIANITA ...................................................................................................................... 56
THERAPEUTIC COMMUNICATION OF DOCTORS AND PATIENTS IN THE DISEASE IN
ANUTAPURA GENERAL HOSPITAL
KOMUNIKASI TERAPEUTIK DOKTER DAN PASIEN PADA BAGIAN PENYAKIT
DALAM DI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU
RENALDO MARTIN KRISTANTO TORILE ........................................................................... 81
SELF-CONCEPT OF CAREER WOMEN IN FAMILY (Case Study of Working Full-Time
Housewives in Palu City)
KONSEP DIRI WANITA KARIR DALAM KELUARGA (Studi Kasus pada Ibu Rumah
Tangga yang Bekerja Penuh di Kota Palu)
SITI MUNIPA KARIONO ........................................................................................................... 95
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 1
INFLUENCE OF ADDITIONAL EMPLOYMENT INCOME (TPP) ON IMPROVING COMPETENCY, PERFORMANCE AND DISCIPLINE OF PUBLIC SERVANT
PENGARUH PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI, KINERJA DAN DISIPLIN PNS
PROVINSI SULTENG
DERRY B. DJANGGOLA1
1 Widyaiswara Utama BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah E-mail:
Naskah diterima : 4 Juni 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
It is generally known, that in improving working ethic effectively, one organization includes local government
has to focus to the basic needs of public servant. In providing the needs and the improvement of public
servants’ welfare, it is needed a reward and compensation for their service which is given to organizations as a
form of motivation given to public servant. As a consequence, Central Sulawesi Governance, compensation is
given besides salary and allowance that has been attached for public servant as well as incentive form namely
Additional Employee Income (TPP). The scheme has been run since 2015. As it is written in the Government
Rules Number 1 Year 2017 about Additional Income for Public Servant. Providing TPP aims as effort in
improving working ethics, discipline, service quality and public servant welfare. As a policy that has run for 3
year, and it has been planned in 2018, it certainly appears in mind about the influence from the implementation
of this policy. This research aims to know and analyze the influence of providing TPP toward public servant
competence improvement in Central Sulawesi, the influence of providing TPP in improvement of working
ethic of public servant, and the influence providing TPP in improvement of public servant discipline. This
research is conducted by using survey method to public servant as TPP recipients by spreading questionnaire
to 98 respondents. The research result shows that providing TPP has influence toward improvement of Central
Sulawesi public servants’ competence, working ethics, and discipline, and the discipline of Public Servant is a
variable, which is influenced strongly by the existent of providing TPP policy..
Keywords : compensation, competence, performance, discipline
Umum diketahui, bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, sebuah organisasi termasuk pemerintah
daerah harus memperhatikan hal yang mendasar yakni pemenuhan kebutuhan PNS. Untuk memenuhi
kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan PNS, maka diperlukan adanya imbalan atau kompensasi atas
jasanya yang diberikan kepada organisasi sebagai bentuk motivasi yang diberikan kepada PNS. Menyadari hal
tersebut, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kompensasi diberikan selain dalam bentuk gaji
dan tunjangan yang sudah melekat pada PNS juga dalam format insentif bernama Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP). Skema ini berjalan sejak tahun 2015. Sebagaimana tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian TPP dimaksudkan sebagai
upaya meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan PNS. Sebagai
kebijakan yang sudah berjalan tiga tahun, dan rencananya berlanjut pada tahun 2018, tentu muncul
keingintahuan akan pengaruh dari penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui
dan menganalisis pengaruh pemberian TPP terhadap peningkatan kompetensi PNS Provinsi Sulawesi Tengah,
pengaruh pemberian TPP terhadap peningkatan kinerja PNS Provinsi Sulawesi Tengah, dan pengaruh
pemberian TPP terhadap peningkatan disiplin PNS Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan dengan
metode survey terhadap PNS penerima TPP melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian TPP berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi, kinerja dan
disiplin PNS Provinsi Sulawesi Tengah, dan disiplin PNS adalah variabel yang terpengaruh paling kuat atas
adanya kebijakan pemberian TPP.
Kata Kunci : kompensasi, kompetensi, kinerja, disiplin
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 2
A. PENDAHULUAN
Permasalahan klasik utama yang dihadapi
oleh alam birokrasi Indonesia adalah terkait
dengan kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Kelemahan atas ketiga hal tersebut masih
merupakan penyakit birokrasi yang sulit
untuk dihilangkan. Banyak faktor yang
mempengaruhi rendahnya tingkat
kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur.
Salah satu yang mengemuka dan paling
banyak diperbincangkan adalah kompensasi
berbentuk finansial yang diberikan oleh
pemerintah sebagai pemberi kerja.
Umum diketahui, bahwa untuk
meningkatkan kinerja yang efektif, maka
sebuah organisasi termasuk pemerintah
daerah harus memperhatikan hal yang paling
utama yakni pemenuhan kebutuhan PNS.
Untuk memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan kesejahteraan PNS, maka
diperlukan adanya imbalan atau kompensasi
atas jasanya yang diberikan kepada organisasi
sebagai bentuk motivasi kepada PNS.
Kebijakan kompensasi penting diperlukan
untuk meningkatkan motivasi PNS dalam
mencapai prestasi kerja yang terbaik. Prinsip
penting dalam sistem manajemen kompensasi
adalah prestasi yang tinggi harus diberi
penghargaan (reward) yang layak dan apabila
melanggar aturan dalam organisasi atau tidak
mencapai target kinerja yang diharapkan
harus pula diberikan sangsi yang adil.
Kekeliruan dalam menerapkan sistem
kompensasi, khususnya sistem penghargaan,
berakibat akan timbulnya demotivasi dan
akan menurunkan kinerja organisasi.
Demotivasi salah satunya berawal dari
ketidakpuasan dikalangan pegawai.
Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem
manajemen kompensasi yang sesuai dengan
kondisi dan karakteristik daerah masing-
masing.
Berdasarkan penelitian, diperoleh fakta
yang menunjukkan bahwa rendahnya
kompensasi pada sejumlah organisasi bisnis
terkemuka di dunia berpengaruh secara
signifikan terhadap pertumbuhan dan daya
kompetitif. Pertumbuhan dan daya kompetitif
organisasi dihasilkan melalui kompetensi
khusus yang diciptakan melalui
pengembangan keterampilan, kekhasan kultur
organisasi, serta pemberian kompensasi yang
adil dan layak yang merupakan bagian dari
sistem proses manajemen. Weatherly (2003)
menemukan sekitar 85 persen dari nilai pasar
perusahaan (kinerjanya) ditentukan oleh SDM.
Artinya, kompensasi mempengaruhi prilaku
kerja pegawai dan berujung pada kinerja
organisasi.
Secara teoritis, dikenal banyak sistem
kompensasi yang diarahkan untuk
memajukan dan meningkatkan kinerja
organisasi. Adanya kompensasi selain akan
meningkatkan kinerja, secara tidak langsung
akan menarik orang di luar organisasi yang
memiliki kemampuan untuk bergabung dalam
organisasi. Diharapkan dengan adanya
kompensasi, kinerja pegawai dapat
ditingkatkan dan organisasi dapat mencapai
tujuannya secara keseluruhan. Atau dengan
kata lain, pemberian kompensasi yang
sepadan, baik secara finansial atau non
finansial akan mempengaruhi kinerja
organisasi.
Menyadari hal tersebut, di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
kompensasi finansial diberikan selain dalam
bentuk gaji dan tunjangan yang sudah melekat
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 3
pada seorang PNS juga dalam format insentif
bernama Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP). Skema ini sudah dijalankan sejak tahun
2015. Sebagaimana tertera pada Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil, pemberian TPP dimaksudkan sebagai
upaya meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas
pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan
PNS.
Sebagai kebijakan yang sudah berjalan
efektif tiga tahun, dan akan dilanjutkan pada
tahun 2018, tentu muncul keingintahuan akan
pengaruh dari kebijakan tersebut. Apakah
telah sampai pada tataran yang diharapkan
dari pemberian TPP tersebut. Atau baru
sekedar mempengaruhi cara berpikir dan cara
kerja pegawai agar lebih berkinerja,
berdisiplin, memberi pelayanan berkualitas
dan mau meningkatkan kompetensi.
Pengalaman birokrasi penulis, yang aktif
bekerja sejak 1981 atau sudah bergelut dengan
birokrasi pemerintahan daerah selama 38
tahun dengan karier jabatan puncak sebagai
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, membiasakan penulis untuk
selalu memantau dan mengevaluasi setiap
kebijakan yang diterapkan. Terlebih kebijakan
yang berkaitan dengan kepegawaian. Penulis
sangat menyadari bahwa aparatur adalah
penggerak birokrasi. Kualitas birokrasi
pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja
aparaturnya sendiri. Olehnya kebijakan
terhadap aparatur menjadi hal yang mutlak
diperhatikan. Termasuk pemberian TPP ini.
Tentunya dalam kerangka untuk perbaikan
dan penyempurnaan kebijakan.
Pemantauan terhadap pengaruh dari
adanya kebijakan pemberian TPP terhadap
perilaku kerja penerima TPP (PNS) semakin
diperlukan, dilihat dari sisi bahwa kebijakan
pemberian TPP yang sudah berjalan 3 Tahun
belakangan, menggunakan dana (APBD) yang
tidak sedikit. Apabila pemberian TPP tidak
mempengaruhi kinerja dan disiplin pegawai,
tentu akan lebih bijak apabila dana tersebut
dimanfaatkan dan dipergunakan pada sektor
publik (belanja langsung) karena dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka
penulis berinisiatif melaksanakan suatu riset
sederhana dengan judul “Pengaruh Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Terhadap Peningkatan Kompetensi, Kinerja
dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi
Sulawesi Tengah”.
B. METODE
Riset tetap menggunakan metode penelitian
yang umum digunakan sehingga hasilnya bisa
menunjukkan realitas yang terjadi. Penelitian yang
dilakukan pada akhir 2017 lalu, menggunakan
metode survey sebagai cara pengumpulan
informasi secara sistematik yang dilakukan
terhadap responden dengan maksud untuk
memahami dan atau meramal beberapa aspek yang
diamati dari responden. Metode survey lebih
memperhatikan pada sampling, desain
kuisioner/interview, administrasi kuesioner dan
analisis data (Malhotra, 2009).
Objek riset atau sebagai populasi penelitian
adalah para PNS penerima TPP yang ribuan
jumlahnya (4.897). Dengan pendekatan (rumus)
Slovin, sampel sebanyak 98 sesuai komposisi
jabatan yang ada, cukup mewakili populasi
tersebut. Terperinci, sampel terdiri atas 1 JPT, 76
pejabat administrasi dan 21 pejabat fungsional.
Sampel inilah yang menjadi sumber data (primer)
melalui pengisian kuesioner yang dirancang
sedemikian rupa mampu menunjukkan pengaruh
adanya TPP terhadap perilaku kerja PNS.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 4
Pengumpulan data lainnya dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi
yang tersedia.
Isian kuesioner (36 butir pertanyaan) dengan
format skala likert (1 – 5 / sangat tidak setuju –
sangat setuju) dari para responden selanjutnya
dilakukan tabulasi sesuai distribusi frekwensi
masing-masing variabel. Ini untuk
mengkuantitatifkan persepsi para responden atau
PNS yang menjadi sampel. Hasil tabulasi
selanjutnya menjadi bahan analisis data dengan
menginterpretasi nilai rata-rata (mean) setiap item
atau butir pertanyaan/pernyataan. Melalui
pemaknaan ini akan memperjelas arah atau
kecenderungan tanggapan responden. Interpretasi
mengikuti pendekatan Sugiyono (2004), 0 ≤ NM <
1,25 Sangat Kecil/Sangat Rendah/Sangat Lemah,
1,25 ≤ NM < 2,50 Kecil/Rendah/Lemah, 2,50 ≤
NM < 3,75 Besar/Tinggi/Kuat, dan 3,75 ≤ NM < 5
Sangat Besar/Sangat Tinggi/Sangat Kuat.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Riset sederhana, yang dalam prosesnya
ternyata tidak semudah dibayangkan ini,
secara ringkas memperlihatkan hasil
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 1.
Rekapitulasi Nilai Mean Variabel Hasil Penelitian
No. NAMA
VARIABEL NAMA INDIKATOR
VARIABEL
NILAI MEAN
INDIKATOR
NILAI MEAN
VARIABEL KETERANGAN
1 KOMPETENSI
Pendidikan 4.222
4.341 SANGAT
TERPENGARUH Keterampilan 4.342
Perilaku 4.459
2 KINERJA
Kebenaran Proses Dan Hasil Kerja
4.352
4.327 SANGAT
TERPENGARUH Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
4.383
Ketepatan Penggunaan Bahan Kerja
4.245
3 DISIPLIN
Kepatuhan Terhadap Waktu Kerja
4.429
4.373 SANGAT
TERPENGARUH
Kepatuhan Terhadap Aturan Disiplin Kepegawaian
4.446
Kepatuhan Terhadap Aturan Internal
4.245
Melalui tabel data di atas, ditunjukkan bahwa
Kompetensi, Kinerja dan Disiplin terpengaruh
secara positif dengan adanya TPP. Dari
ketiganya, disiplin menjadi variabel yang
secara kuat terpengaruh. Merujuk pada
Pergub No. 1 Tahun 2017 tentang TPP yang
memang memberi porsi sebesar 70% nominal
TPP yang akan diterima seorang PNS berasal
dari kepatuhannya terhadap jam kerja
(disiplin waktu), maka ini menjadi temuan
yang lumrah. Adapun nilai mean variabel
kinerja sebagai nilai terkecil diantara nilai
mean variabel lainnya, menandakan masih
diperlukan upaya pembenahan dan perbaikan
terhadap pola pembinaan kepada pegawai
agar lebih berkinerja.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 5
Pengaruh Pemberian TPP Terhadap Kompetensi
Penelusuran dan keterbatasan penulis,
belum mendapat informasi yang utuh terkait
dampak pemberian kompensasi terhadap
peningkatan kompetensi. Temuan justru
didominasi oleh kondisi yang menunjukkan
bahwa kompensasi dan kompetensi (secara
bersamaan) sebagai faktor yang
mempengaruhi kinerja aparatur.
Dimasukkannya variabel ini dalam riset
dengan maksud untuk melihat pemahaman
pegawai akan arti pentingnya kompetensi bagi
keberhasilan pelaksanaan tugas dan
jabatannya. Juga pengetahuan pegawai akan
faktor pembentuk kompetensi yaitu
pendidikan, keterampilan dan sikap perilaku.
Sekiranya menjadi hal yang diperlukan,
dikaitkan dengan adanya TPP, akankah
menjadi sarana untuk meningkatkan
kompetensi.
TPP adalah wujud dari kompensasi
langsung dalam nominal rupiah yang
terjadwal bulanan. Dengan demikian secara
langsung menambah penerimaan bulanan
pegawai. Penambahan ini berarti
meningkatkan daya beli termasuk
memunculkan hasrat belanja atau konsumsi
baru. Bagi pegawai yang menyadari
pentingnya kompetensi dan mengetahui
faktor pembentuk kompetensi (pendidikan,
keterampilan dan sikap perilaku) maka
pembelanjaan penghasilannya boleh jadi
sebagian akan diarahkan pada peningkatan
kompetensi.
Penelitian ini menemukan jika dikalangan
pegawai telah terbentuk pemahaman yang
kuat akan pentingnya kompetensi. Dan
adanya TPP (antara lain) akan digunakan
untuk meningkatkan kompetensi. Baik dengan
melanjutkan pendidikan atau menambah
keterampilan tertentu. Nilai mean 4.341,
menunjukkan kuatnya hal tersebut.
Temuan ini tentunya merupakan hal yang
positif. Dialokasikannya sebagian penghasilan
pegawai, yang didalamnya termasuk TPP,
untuk melanjutkan pendidikan atau
mengikuti kursus keterampilan tertentu, maka
dimasa datang akan semakin banyak aparatur
Provinsi Sulawesi Tengah yang berkompeten.
Hal positif lain yang diperoleh dari
penelitian ini adalah sikap aparatur yang
secara tegas menolak korupsi. TPP menjadi
salah satu pemicunya. Dengan demikian,
harapan untuk mencapai pemerintahan yang
bersih dari tindakan korupsi bukanlah hal
yang mustahil.
Pun begitu, pada riset ini terdapat 40
responden (40.8%) yang ragu-ragu (20) bahkan
tidak setuju (20) menggunakan TPP untuk
melanjutkan pendidikan. Ini berkesan anomali
dengan sangat kuatnya pemahaman terhadap
pentingnya pendidikan. Untuk ini, penjelasan
yang bisa diberikan ialah boleh jadi mereka
adalah pegawai penerima TPP yang
menganggap jenjang pendidikannya saat ini
sudah cukup memadai. Memang karakteristik
pendidikan responden didominasi pegawai
berpendidikan S1 dan S2.
Penjelasan lainnya adalah, boleh jadi,
mereka merupakan pegawai yang walau
secara kuat memahami pentingnya
pendidikan tapi masih memiliki kebutuhan
atau kepentingan lain dan lebih prioritas yang
ditutupi menggunakan TPPnya. Pemakluman
akan situasi ini sangat beralasan dengan
melihat mayoritas responden (89.80%) adalah
pegawai yang sudah berkeluarga.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 6
Keunikan temuan juga terjadi pada
indikator kedua dari variabel kompetensi.
Yakni munculnya keraguan dan
ketidaksetujuan TPP digunakan untuk
meningkatkan keterampilan. Adanya temuan
ini boleh jadi karena ketidakpahaman pegawai
bersangkutan akan jenis keterampilan yang
perlu baginya. Berbeda dengan pendidikan
yang jelas klasifikasinya (diploma, sarjana
atau pascasarjana) dan melalui lembaga
formal, maka keterampilan memang masih
bersifat umum dan terkadang bisa dipelajari
secara otodidak. Kalaupun melalui pelatihan,
lembaga pelatihan pun begitu beragam dan
berstatus non formal.
Ketidakpahaman pegawai akan jenis
keterampilan yang perlu baginya selanjutnya
memunculkan kesan masih adanya pegawai
yang tidak atau belum diberikan tugas atau
pekerjaan yang jelas dan terukur dari
pimpinan atau pembina kepegawaian dalam
instansinya. Jika benar adanya maka
diperlukan terobosan kebijakan bidang
manajemen kepegawaian agar semua pegawai
memiliki kejelasan tugas dan pekerjaan yang
harus dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan.
Pengaruh Pemberian TPP Terhadap Kinerja
Mathis dan Jackson (2002) menyatakan
bahwa salah satu cara untuk meningkatkan
prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan
kinerja para karyawan adalah melalui
kompensasi. Penelitian ini ternyata seirama
dengan pernyataan tersebut. Aparatur
Provinsi Sulawesi Tengah terpengaruh untuk
berkinerja atas adanya kompensasi berupa
TPP. Deteksi melalui nilai mean menunjukkan
angka 4.327.
Variabel kinerja diukur melalui item
kebenaran proses hasil kerja, ketepatan waktu
pelaksanaan pekerjaan dan ketepatan
penggunaan bahan kerja. Tanggapan
responden sampai pada NM 4.327
menunjukkan bahwa pemberian TPP
memberikan pengaruh yang sangat baik
kepada kinerja. Pegawai termotivasi dan
semakin bergairah dalam bekerja. Tentunya
ini adalah hal yang harus dipelihara dan terus
ditingkatkan.
Merujuk pada berbagai penghargaan yang
diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah pada 2015 sampai 2017 semakin
memperkuat tesis tersebut. Akan sangat
panjang jika raihan itu disampaikan pada
artikel yang terbatas ini. Yang pasti prestasi
tersebut adalah buah kerja dari personal
aparatur.
Perlu diperhatikan, walau masih dalam
rentang nilai mean yang tinggi, tapi NM
variabel ini adalah terkecil dibanding NM
variabel lainnya. Ini menunjukkan masih ada
unsur lain yang bisa mempengaruhi pegawai
untuk lebih berprestasi. Peneliti lain
diharapkan bisa mengungkap hal ini dimasa
datang.
Pengaruh Pemberian TPP Terhadap Disiplin
Pemberian TPP sangat mempengaruhi
disiplin pegawai. Ini dibuktikan dengan NM
yang mencapai 4.373. NM terbesar diantara
NM variabel lainnya. Pergub No. 1 Tahun
2017 tentang TPP memang mengisyaratkan
bahwa 70% nominal TPP yang akan diterima
seorang PNS berasal dari kedisiplinannya
mematuhi jam kerja. Setidaknya salah satu
maksud dari adanya TPP, yakni
meningkatkan disiplin aparatur, telah
tercapai.
Hasil demikian sudah disinyalir
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 7
sebelumnya oleh Malayu Hasibuan (2008),
yang mengemukakan delapan tujuan
pemberian kompensasi, satu diantaranya
adalah untuk meningkatkan disiplin.
Menurutnya, dengan pemberian balas jasa
yang cukup besar maka disiplin karyawan
semakin baik. Mereka akan menyadari dan
menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
Temuan empiris terkait disiplin PNS
lingkup Prov. Sulteng rentang 2015 – 2017
atau saat kebijakan TPP diterapkan juga
mendukung. Izin cerai PNS yang diterbitkan
BKD Prov. Sulteng mengalami degradasi. Dari
23 perceraian pada 2015 menjadi 19 di 2017.
Penjatuhan hukuman disiplin PNS juga turun
sepertiga. 12 di 2016 menjadi 8 di 2017.
Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut
adalah sekiranya pada masa akan datang
komposisi pembentuk nilai TPP mengalami
perubahan. Saat ini komposisinya adalah 70%
dari perilaku kerja (disiplin waktu kerja) dan
30% dari prestasi kerja (kinerja). Dengan
komposisi demikian, lumrah jika pegawai
mengejar atau termotivasi untuk mematuhi
waktu kerja. Olehnya ketika perbandingan ini
mengalami perubahan perlu dilakukan
penelitian kembali.
Walhasil, dapat ditetapkan bahwa
kebijakan pemberian TPP oleh Provinsi
Sulawesi Tengah berpengaruh secara kuat
terhadap pola pikir, pola tindak dan pola kerja
pegawai. Dalam hal ini berupa atau
ditunjukkan dengan kuatnya keinginan untuk
meningkatkan kompetensi, termotivasinya
pegawai secara kuat untuk bertindak disiplin
dalam dimensi yang lebih luas tidak saja pada
disiplin waktu, serta terdorongnya pegawai
secara kuat pula untuk bekerja lebih
berkualitas bahkan dalam area yang lebih
spesifik seperti bersemangat untuk melayani.
D. KESIMPULAN
Riset yang penulis yakini masih jauh dari
kesempurnaan ini, menemukan bahwa
kebijakan pemberian TPP ternyata mampu
mempengaruhi kompetensi, kinerja dan
disiplin PNS Provinsi Sulawesi Tengah.
Disiplin PNS menjadi area yang terpengaruh
paling kuat atas adanya kebijakan pemberian
TPP. Riset ini menunjukkan bahwa sebagian
dari harapan filosofis kebijakan pemberian
TPP, yakni pemberian TPP dimaksudkan
sebagai upaya meningkatkan kinerja, disiplin,
kualitas pelayanan dan meningkatkan
kesejahteraan PNS, telah tercapai.
Saran yang dapat disampaikan antara lain
adalah :
1. Kebijakan pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) seyogyanya
dilanjutkan. Kebijakan ini ternyata
berdampak positif bagi pola pikir dan pola
kerja pegawai. Tentunya dengan tetap
melakukan evaluasi, perbaikan dan
penyempurnaan.
2. Sekiranya komposisi pembentuk nominal
TPP yang diterima seorang PNS akan
berubah, saat ini 70% perilaku kerja
(kehadiran) dan 30% prestasi kerja
(kinerja), maka perubahannya sebaiknya
secara bertahap untuk mencapai komposisi
ideal (berimbang atau lebih didominasi
unsur kinerja). Di 2018, penulis
merekomendasikan 60% dari kehadiran
dan 40% dari kinerja.
3. Perlunya pemetaan atau penelusuran
minat dan bakat aparatur yang ada di
lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Ini
sebagai informasi dan bahan untuk proses
penempatan/distribusi pegawai. Adanya
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 8
data ini, pegawai bisa ditempatkan sesuai
minat bakatnya. Organisasi akan terisi oleh
pegawai yang kompetensinya seirama
dengan tugas dan fungsi organisasi. Dan
aparatur juga bisa nyaman bekerja atau
bisa memastikan jenis pendidikan atau
keterampilan apa yang akan
dikembangkannya. Keberadaan TPP
tentunya akan semakin bermakna. UPT
Penilaian Kompetensi Pegawai BKD
Provinsi Sulawesi Tengah sudah
memenuhi syarat untuk melakukan itu.
4. Terkait nilai mean dari variabel kinerja
menjadi yang terkecil diantara variabel
lainnya memunculkan dugaan masih
adanya faktor lain yang bisa
mempengaruhi kinerja pegawai Provinsi
Sulawesi Tengah. Olehnya peneliti lain
diharapkan dapat menindaklanjutinya
dimasa datang.
E. DAFTAR PUSTAKA
Augusty, Ferdinand. (2010). Metode Penelitian
Manajemen: Pedoman Pendidikan
Penelitian untuk Ilmu Skripsi, Tesis dan
Disertasi Ilmu Manajemen.Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur
Penelitian suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. (2017). Statistik Kepegawaian
Oktober 2017.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi
Tengah. (2017). Sulawesi Tengah Dalam
Angka Tahun 2017.
Dessler, Gary. (2003). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Jakarta: PT Prehalindo.
Dharma, Surya. (2004). Manajemen Kinerja :
Falsafah, Teori, dan Penerapannya.
Jakarta: Progam Pascasarjana FISIP.
Djati, S., Pantja. Dan Khusnaini, M., (2003).
“Kajian Terhadap Kepuasan Kompensasi,
Komitmen Organisasional Dan Prestasi
Kerja.” Jurnal Manajemen dan
Kewirausahaan, Vol.5, No 1, Maret, ha; 25-
41
Handoko, T., Hani. (2008). Manajemen
Personalia dan Sumber Daya Manusia,
Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Hartono. (2002). “Pengaruh Kepuasan
Komunikasi Dalam Kegiatan Perusahaan
Terhadap Komitmen Kerja Karyawan
Pada Kantor Inspeksi PT Bank RI (Persero)
Denpasar”. Thesis Tidak Diterbitkan.
Magister Manajemen Universitas Gadjah
Mada.
Hariandja, Marihot Tua Efendi. (2002).
Manajemen Sumber Daya Manusia:
Pengadaan, Pengembangan,
Pengkompensasian dan Peningkatan
roduktivitas Pegawai. Jakarta:Grasindo.
Hasibuan, SP. Malayu. (2005). Manajemen
Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Askara.
Hasibuan, SP. Malayu. (2008). Manajemen
Sumber Daya Manusia.Jakarta: Bumi
Askara,
Malhotra, Naresh K, 2009. Riset Pemasaran :
Pendekatan dan Terapan, Edisi Bahasa
Indonesia. Jakarta: PT. Indeks Kelompok
Gramedia.
Malthis dan Jackson. (2002). Manajemen
Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama.
Cetakan Pertama. Yogyakarta : Salemba
Empat
Milkovich, George and Jerry Newman.
(2008). Compensation. USA: Ninth
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 9
Edition.
Mulyadi. (2008). Akuntansi Manajemen, Edisi
Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba
Empat
Prawirosentono, Suyadi. (1999). Kebijakan
Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
Rivai, Veithzal. (2004). Manajemen Sumber
Daya Manusia untuk Perusahaan Teori
Praktek. Jakarta: Raja Grafindo.
Rivai Veithzal & Jauvani Ella. (2009).
Manajemen Sumber Daya Manusia untuk
Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo.
Sekaran, U. (2006). Research Method For
Business. Jakarta: Salemba Empat.
Simamora, Henry. (2004). Manajemen
Sumber Daya Manusia, Edisi
Tiga.Yogyakarta: STIE YKPN.
Sugiyono dan Wibowo. (2002). Statistik
Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. (2004). Statistika Untuk Penelitian.
Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV
Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
Universitas Negeri Yogyakarta. (2009).
Pedoman Penulisan Tugas Akhir.
Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta
Umar, Husein. (2002). Riset Sumber Daya
Manusia Dalam Organisasi, Edisi Revisi
dan Perluasan. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Weatherly, L.A. (2003). The Value of People:
The Challenges and Opportunities of
Human Capital Measurement and
Reporting. Society for Human Resource
Management Research Quarterly.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 10
POLICY OF TERITORIAL AND REGIONAL REGULATION OPPORTUNITIES IN CENTRAL SULAWESI
KEBIJAKAN REFORMASI TERITORIAL DAN PELUANG PEMEKARAN DAERAH DI SULAWESI TENGAH
RIZALI DJAELANGKARA1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sulawesi Tengah E-mail:
Naskah diterima : 3 Mei 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
In the development of government and territorial growth of a region in a country there are three things that are likely to occur related to territorial / regional structuring reform policies, first, the area is broader because the second centripetal policy has merged or annexed due to fragmentation. territorial (centrifugal policy), third, with the same territorial area (static / constants policy). in post-reform Indonesia in 1998 there have been an increase of 223 new autonomous regions (DOB) from a total of 319 pre-reform autonomous regions to 542 autonomous regions at the provincial / district / city level after the reformation. For Central Sulawesi, there are 23 proposals / plans for the establishment of DOBs. For projections and strategies to address the issue of regional expansion in Central Sulawesi based on current conditions and dynamics (2018), appropriate policy choices are needed in the face of the growing phenomenon of demand for expansion / formation of DOBs and regional structuring strategies based on centripetal policy, centrifugal policy or Constants policy . Judging from the strength of the Centripetal policy (integrated direction) there are a number of choices in the form of Annexation, Consolidation, Amalgamition. While the Centrifugal policy in the form of policies of Detachment, Fragmentation, Proliferation, Regional Government Splitting, Partition and Political Sub Division. For Constants / static policy choices in which the government carries out a pemekaran moratorium on an ongoing basis with proactive policy instruments. To project opportunities for DOB formation in Central Sulawesi, (1) Proposal for the establishment of Moutong and Tomini Raya Districts is more likely to be realized, as seen from the process, the two DOB candidates have been approved as DOBs as proposed by the DPR-RI initiative. East has the opportunity, because the proposal of the area at the regional level has been completed. (3) Areas that are actually and factually truly for reasons of distance of service and / or because of consideration of having national strategic values and security can have opportunities for form. Keywords : territorial reform, centripetal policy, centripetal policy, constants policy Dalam perkembangan pertumbuhan pemerintahan dan teritorial suatu daerah dalam suatu negara ada tiga hal kemungkinan terjadi yang berkaitan dengan kebijakan reformasi teritorial/penataan daerah, pertama, daerah semakin luas karena terjadi penggabungan atau aneksasi wilayah sekitarnya (centripetal Policy) kedua, semakin mengecil wilayahnya karena terjadi fragmentasi teritorial (centrifugal Policy), ketiga, dengan kondisi luasan teritorial yang sama (static/constants Policy). di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 telah terjadi penambahan sebanyak 223 daerah otonom baru (DOB) dari total 319 daerah otonom pra-reformasi menjadi 542 daerah otonom setingkat provinsi/kabupaten/kota pasca reformasi. Untuk Sulawesi Tengah, wacana/rencana untuk pembentukan DOB sebanyak 23 usulan DOB. Untuk proyeksi dan strategi menghadapai isu pemekaran daerah di Sulawesi Tengah berdasarkan kondisi eksiting dan dinamika sekarang ini (2018), diperlukan pilihan kebijakan yang tepat dalam menghadapi berkembangnya fenomena permintaan untuk dimekarkan/pembentukan DOB serta strategi penataan daerah berbasis centripetal policy, centrifugal policy atau Constants policy. Dilihat dari kekuatan Centripetal policy (arah menyatu/memusat) terdapat sejumlah pilihan dalam bentuk Annexation, Consolidation, Amalgamition. Sedangkan Centrifugal policy dalam bentuk kebijakan Detachment, Fragmentation, Proliferation, Regional Government Splitting, Partition dan Political Sub Division. Untuk pilihan kebijakan Constants/static di mana pemerintah melakukan moratorium pemekaran secara berkelanjutan dengan policy instrument yang proaktif. Untuk Proyeksi peluang pembentukan DOB di Sulawesi Tengah, (1) Usulan Pembentukan Kabupaten Moutong dan Tomini Raya lebih berpeluang untuk diwujudkan, karena dilihat dari prosesnya, kedua calon DOB tersebut sudah disahkan menjadi DOB sebagai usul inisiatif DPR-RI, (2) Usulan Pembentukan Sulawesi Timur berpeluang, karena usulan daerah tersebut pada tingkat daerah sudah selesai. (3) Daerah-daerah yang secara nyata dan faktual benar-benar karena alasan jarak pelayanan dan atau karena pertimbangan punyai nilai strategis nasional dan keamanan dapat memiliki peluang untuk bentuk. Kata Kunci: reformasi teritorial, centripetal policy, centrifetal policy, constants policy
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 11
A. PENDAHULUAN
Dalam perkembangan pertumbuhan
pemerintahan dan teritorial suatu daerah
dalam suatu negara atau pemerintahan ada
tiga hal kemungkinan terjadi, pertama, daerah
semakin luas karena terjadi penggabungan
atau aneksasi wilayah sekitarnya (centripetal
policy) kedua, semakin mengecil wilayahnya
karena terjadi fragmentasi teritorial
(centrifugal policy), ketiga, dengan kondisi
luasan teritorial yang sama (static/constants
policy).
Khusus di Indonesia sejak bergulirnya
reformasi tahun 1998 yang disusul pula
adanya ephoria reformasi teritorial, sejak
tahun 1999 telah terjadi penambahan
sebanyak 223 daerah otonom baru dari total
319 daerah otonom pra-reformasi menjadi 542
daerah otonom setingkat
provinsi/kabupaten/kota pasca reformasi.
(Kemendgari 2017).
Sumber Kemendagri 2017, diolah validasi
kembali oleh Penulis
Khusus Provinsi Sulawesi tengah,
berdasarkan data/informasikan yang
disampaikan oleh Gubernur Sulteng pada
acara sosialisasi tentang Kebijakan Penataan
Daerah pada bulan November 2016, diperoleh
gambaran sebagai berikut.
Tabel di atas menunjukan bahwa dari 14
Daerah Otonom (DO) yang ada di Sulawesi
Tengah sekarang, telah diwacanakan kembali
Tabel 1 Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten/Kota/Provinsi Di Rpovinsi Sulawesi
Tengah Periode 2012-Sekarang
Sumber: Sambutan Gkdh Pada Acara Sosialisasi Tentang Kebijakan Penataan Daerah Tanggal 24
November 2016 Di Palu, Diolah Kembali
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 12
untuk pembentukan 13 Daerah Otonom Baru
(DOB), baik sebagai pemekaran daerah
provinsi, Kabupaten, maupun perubahan
stutus kota. Sementara pada Tahun 2011, di
masa Kepempinan Gubernur HB Paliudju,
Pemerintah Sulawesi Tengah telah melakukan
kajian desain penataan daerah Sulawesi
Tengah 2011-2025, yang didasarkan pada
kebutuhan wilayah, kondisi geografis,
kependudukan dan potensi wilayah serta
SDA. Dalam grand desain yang sudah
digodok pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah hingga 2025 mendatang, akan
dibentuk sedikitnya 20-an kabupaten
termasuk 10 wilayah otonom kabupaten/kota
yang sudah ada selama ini, Grand Design
pemekaran tersebut bahkan sudah dikirimkan
ke Mendagri.
Mengenai perbandingan jumlah daerah
otonom dengan luas wilayah/jumlah
penduduk pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi
seperti ada tabel di bawah.
Berdasarkan Luas Wilayah masing-masing
provinsi yang ada di pulau Sulawesi
berdasaskan data pada Provinsi Dalam
Angka tahun 2017, dari kelima provinsi
memiliki luas 188.747,7 Km2, dari luas
tersebut luas Provinsi Sulawesi Tengah
sebesar 32,7% dari total luas pulau Sulawesi
dengan jumlah daerah otonom yang dibawahi
otonomi provinsi ini sebanyak 12 Kabupaten
dan satu Kota. Dari perbandingan luas
wilayah tersebut secara kasat mata dapat
dikatakan Provinsi Sulawesi Tengah masih
memungkinkan untuk dimekarkan.
B. PERMASALAHAN
Berangkat dari tema tulisan ini yang
berjudul Kebijakan Penataan Daerah dan
Peluang Pemekaran Daerah di Provinsi
Sulawesi Tengah, secara prospektif
berdasarkan kondisi perkembangan
pemerintahan/pembangunan, ekonomi,
politik serta sosial budaya dan teknologi
sesuai dinamika kondisi eksiting tahun 2017,
maka penulis memfokuskan pada Tiga (3)
masalah yang menjadi dasar pembahasan
dalam menjawab makna denotatif dari tema
tersebut, yaitu:
Tabel 2: Perbandingan Luas Wilayah/Jumlah penduduk dengan Jumlah Daerah Otonom/Baru
Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi
Sumber: BPS, Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi Dalam Angka, 2017
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 13
1. Apa pilihan Kebijakan penataan
daerah oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah
berkaitan dengan berkembangnya fenomena
permintaan untuk dimekarkan/pembentukan
DOB.
2. Strategi Apa yang harus ditempuh
oleh pemerintah daerah, jika pilihan kebijakan
harus bermuara pada strategi penataan
daerah yang berbasis centripetal policy,
centrifugal policy ataupun constants/Static
policy.
3. Berdasarkan Kondisi yang ada dan
pilihan kebijakan yang ditempuh, usulan
pembentukan DOB mana yang plausible dan
berpeluang untuk difasilitasi
pembentukannya.
C. TINJAUAN SINGKAT TEORI TENTANG
PENATAAN DAERAH
1. Konsep Teoritik tentang Pemekaran
sebagai bagian dari reformasi teritorial
Pendapat yang komprehensif dan
aplikatif relevan dengan Kebijakan Pemekaran
di Indoensia adalah pendapat dari Ferrazzi,
yang mengatakan:
reformasi administrasi teritorial adalah
pengelolaan atas ukuran, bentuk dan hirakhi
dari unit daerah yang bertujuan untuk
mencapai sasaran-saran politik dan
administratif. Struktur teritorial atau
pembagian teritorial mengacu pada
pengaturan tingkatan dan jumlah/ukuran
unit. Administrasi teritorial dianggap sebagai
aplikasi tambahan dari alat dan kebijakan
yang untuk penyesuaian unit teritorial,
sedangkan reformasi teritorial dianggap
sebagai reorganisasi yang lebih mendasar
(dari jumlah unit atau tingkatan pemerintah)
atau perbaikan dari alat-alat dan kebijakan
yang dipergunakan untuk mengatasi
struktur/pembagian teritorial.
2. Bentuk-bentuk Kebijakan Penataan Daerah
Dilihat dari kekuatan Centripetal policy
(arah menyatu/memusat) terdapat sejumlah
istilah yng berkembang yaitu:
a) Annexation (Aneksasi), Sebuah
masyarakat atau daerah memperluas
batas-batasnya dengan memasukan
wilayah tertentu di sekitarnya menjadi
bagian dari wilayahnya (True Blood,
1994).
b) Consolidation, Penggabungan dua
atau lebih komunitas/daerah yang
ada membentuk satu daerah baru
yang ukurannya lebih besar (Pawel
Swianiwicz, 2010).
c) Amalgamition Penggabungan dari
dua atau lebih daerah yang ukuran
kecil yang setingkat menjadi daerah
otonom yang lebih luas (Mabuchi,
2001)
Dilihat dari kekuatan Centrifugal (mekar
dan memencar) terdapat sejumlah istilah yng
berkembang yaitu:
a) Detachment, Pemisahan dari dari
bagian suatu daerah/komunitas
menjadi daerah/komunitas
tersendiri.(True Blood, 1994)
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 14
b) Fragmentation (Pawel Swianiwicz,
2010), Perluasan atau penyebaran
Pemerintahan di tingkat bawah dalam
bentuk daerah otonom baru yang
dimekarkan dari sebuah daerah
otonom induk.
c) Proliferation (Bappenas, 2008),
Perluasan atau penyebaran
Pemerintahan di tingkat bawah dalam
bentuk daerah otonom baru yang
dimekarkan dari sebuah daerah
otonom induk.
d) Regional Government Splitting
(Ferrazzi, 2007), sama dengan konsep
proliferasi di atas.
e) Partition, Pemilah-milahan suatu
bagian dari suatu negara menjadi
beberapa negara atau menjadi
beberapa bagian/tingkatan daerah
dalam suatu negara. (Brendan O,
Leary, 2007)
f) Political Sub Division, penataan dan
pembentukan sususan wilayah dalam
suatu negara ke dalam beberapa
bentuk tingkatan dan jenis baik
vertikal maupun horizontal
(Maximilian Auffhammer, 2003)
Antara dua kekuatan pertumbuhan dan
perkembangan pemerintahan daerah tersebut
dikenal pula model jalan tengah atau disebut
oleh Robert Hertzog sebagai Intermunicipal
Cooperation (IMC) , model yang dianggap
cukup berhasil dikembangkan di Perancis,
yakni suatu kondisi yang terdiri dari ragam
pihak (pemerintah daerah) yang bersepakat
untuk melakukan kerjasama yang menghasil
barang dan jasa tertentu yang dapat
dimanfaatkan oleh kedua belah, dengan biaya
yang diperlukan telah disepakati sebelumnya.
Penyediaan barang dana jasa atau urusan
pemerintahan tersebut dilakukan dengan
pertimbangan akan lebih memadai jika
dilakukan melibatkan raga pihak dengan
tidak berpengaruh kepada otoritas wilayah
dan pemerintah masing-masing pihak.
4. Alasan Argumentatif Teoritik Pro
Pemekaran dan Pro Penggabungan
Menurut Reiljan, terdapat empat alasan
argumentatif mengapa relevan pilihan
kebijakan reformasi teritorial
memprioritaskan pembentukan wilayah yang
lebih besar (penggabungan/Amalgamation
/Consolidation/Centripetal),
1) Suatu daerah yang memiliki ukuran
yang lebih besar lebih efisien secara
ekonomi.
2) Di dalam daerah yang berukuran
besar, proses politik lebih demokratis
lebih mudah diwujudkan;
3) Pada daerah yang besar potensi
keragaman budaya yang ada apabila
dikelola dengan baik maka menjadi
modal sosial yang besar dalam
pembangunan.
4) Pada daerah yang berukuran besar
lebih memungkinkan peluang untuk
mempromosikan pembangunan
ekonomi.
5) Daerah yang besar akan lebih mampu
menyediakan secara berkualitas dan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 15
adil pemberian layanan, tugas dan
beban pajak .
Berlawanan dengan pandangan di atas
para pendukung konsep Territorial
Fragmentation [Jones, Stewart, 1983] dan para
penganut public choice, walapun mereka
berangka dari beragam asumsi namun para
ahli tersebut bersepakat pada kesimpulan
bersama bahwa “kecil itu Indah” (small is
beautiful), adapun argumen mereka bahwa
fragmentasi (pemekaran daerah) lebih
mentguntungkan dari pada penggabungan
(Consolidation) adalah sebagai berikut.
1. Pada daerah yang lebih kecil,
komunikasi dan akses terhadap
layanan pemerintahan dan
pembangunan yang berkualitas lebih
mudah dilakukan;
2. Program/Kebijakan pembangunan
akan lebih bersifat menjurus sesuai
dengan kondisi lokal karena sifat
kelolkalannya cenderung semakin
homogen.
3. Makna suara pemilih akan lebih
dihargai dan kontrol pemilih terhadap
wakil/orang yang dipilihnya lebih
mudah dilakukan;
4. Dengan fragmentasi akan mendorong
kompetisi antara intitusi
pemerintahan lokal karena jumlahnya
semakin bertambah.
5. Kreasi, kearifan dna inovasi akan
lebih mudah terjadi
D. PEMBAHASAN
1. Tinjauan Fakta dan Alasan Usul Pemekaran
Pembentukan DOB
Untuk Indonesia beberapa alasan faktual
urgensi perlunya pemekaran/pembentukan
DOB baik oleh Pemerintah maupun para
pengusul, di antaranya:
1. Kebutuhan untuk pemerataan
ekonomi daerah. Menurut data IRDA,
kebutuhan untuk pemerataan
ekonomi menjadi alasan paling
populer digunakan untuk
memekarkan sebuah daerah.
2. Kondisi geografis yang terlalu luas.
Banyak kasus di Indonesia, proses
delivery pelayanan publik tidak
pernah terlaksana dengan optimal
karena infrastruktur yang tidak
memadai. Akibatnya luas wilayah
yang sangat luas membuat
pengelolaan pemerintahan dan
pelayanan publik tidak efektif.
3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan
perbedaan identitas (etnis, asal muasal
keturunan) juga muncul menjadi salah
satu alasan pemekaran. Tuntutan
pemekaran muncul karena biasanya
masyarakat yang berdomisili di
daerah pemekaran merasa sebagai
komunitas budaya tersendiri yang
berbeda dengan komunitas budaya
daerah induk.
4. Kegagalan pengelolaan konflik
komunal. Kekacauan politik yang
tidak bisa diselesaikan seringkali
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 16
menimbulkan tuntutan adanya
pemisahan daerah.
Sedangkan berdasarkan penelitian
desktop yang dilakukan oleh Syarifuddin
terhadap kajian dari 36 Studi tentang
pemekaran daerah yang dilakukan oleh
beragam pihak diseluruh wilayah Indonesia
periode 1999-2009, secara empiris, pemekaran
daerah yang terjadi di Indonesia selama ini
dari aspek politik baik di level pusat maupun
daerah menurut Syarifudin terlihat ada 4
makna subtantif politik di level pusat
mengenai pemekaran daerah, yakni: (1) Politik
memecah belah konsentrasi separatis; ( 2)
Politik percepatan pembangunan; (3) Politik
desentralisasi; dan (4) Politik menjaga
integrasi NKRI. Ada 7 makna subtantif politik
di level daerah mengenai pemekaran daerah,
yakni: (1) Politik peningkatan kesejahteraan;
(2) Politik peningkatan layanan publik; (3)
Politik desentralisasi; (4) Politik mengatasi
rentang kendali; (5) Politik pembangunan
wilayah; (6) Politik percepatan pembangunan;
dan (7) Politik kelembagaan (aspirasi forum
desa). Ada 7 makna bias/dissubtantif politik
di level daerah mengenai pemekaran daerah,
yakni: (1) Politik identitas etnis; (2) Politik
identitas agama; (3) Politik kontestasi elite
lokal; (4) Politik pengembalian kejayaan
sejarah; (5) Politik involusi administrasi; (6)
Politik free rider (ditunggangi); dan (7) Politik
uang. Dan ada 4 makna bias/dissubtantif
politik di level pusat mengenai pemekaran
daerah, yakni; (1) Politik penghisapan sumber
daya lokal; (2) Politik mencari popularitas; (3)
Politik partai memenangkan pemilu; dan (4)
Politik uang
2. Pilihan Strategi Penataan Daerah di
Sulawesi Tengah
a. Pilihan Kebijakan Centrilfugal/Fragmentasi
(Memfasilitasi Pemekaran)
Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
memiliki kepedulian dan goodwill dan
political will untuk memfasilitasi pemekaran
daerah, maka pemerintah daerah harus
memiliki langkah/tahapan strategis yang
mencakup:
1) Harus bersifat eklektik, artinya
memilih prioritas dari sejumlah
daerah usulan baru yang berpeluang
lebih besar untuk dapat
diperjuangkan, baik dilihat dari
proses tahapan yang telah ditempuh
dalam proses pengusulan rencana
DOB bersangkutan maupun fakta
alasan pemekaran berasarkan demand
dan suplay.
2) Konsolidasi dalam bentuk enabling
setting dan polycentris facilitative,
artinya dari sejumlah wacana daerah
yang hendak dimekarkan, pemerintah
di daerah harus melakukan
konsolidasi, baik membangun
komunikasi dan kesamaan persepsi
tentang urgensi, relevansi, kajian dan
pemenuhan persyaratan dan sediaan
sumber daya dan jaringan perjuangan
untuk itu. Konsolidasi yang dimaksud
melibatkan pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten Induk/Asal,
masyarakat setempat, Partai
Politik/anggota DPRD Daerah,
DPR/DPD utusan Sulawesi Tengah
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 17
dan ragam pihak pemangku
kepentingan lainnya, termasuk
pembentukan/penguatan desk-work
khusus bagi kebijakan pemekaran di
daerah.
3) Proaktif antisipasi dalam
meminimalisasi konflik akibat rencana
pemekaran serta segala hambatan
internal maupun eksternal, termasuk
upaya persiapan sosial, infrastruktur
pemerintahan dll.
4) Secara denotatif menegaskan
komitmen tentang penataan daerah
melalui kebijakan nyata dan eksplisit
dalam perencanaan program dan
pembiayaan pembangunan daera.
5) Selalu memperhatikan politic signal,
policy streaming dan policy windows
dari pemerintah pusat terhadap
kebijakan pemekaran daerah.
b. Pilihan Kebijakan Centripetal/Amalgamasi
/Penggabungan Daerah
Dalam ketentuan undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemekaran
Daerah dibahas dalam Bab-VI mulai dari Pasal
31 sampai pasal 56 dengan nomenklatur
“Penataan Daerah”, berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang tersebut, berbicara
penataan daerah tidak saja hanya fokus pada
upaya pemekaran, tetapi juga berbicara
penggabungan daerah (Proses/Tahapan
Pemekaran sesuai UU No.23 Tahun 2014
terlampir). Sayangnya selama ini baik para
politisi, pemerintah, akademisi, msyarakat
luas bahkan kebijakan operasional tenteng
penataan daerah tidak ada yang mengatur
khusus dan mendorong peluang terjadinya
penggabungan daerah.
Jika kita membandingkan dengan
kecenderungan dan pola reformasi teritorial
di beberapa negara, seperti laporan hasil
kajian yang dilakukan oleh Masaru Mabuchi
di Jepang dan hasil kajian yang dilakukan
oleh Pawel Swianiewicz pada sejumlah
negara di Eropa, serta hasil kajian yang
dilakukan oleh Gabriele Ferrazzi pada
sejumlah negara di dunia , justru yang
dominan adalah pilihan penggabungan
dalam bentuk Amalgamasi/Konsolidasi
(centripetal policy) dari pada fragmentasi
(Centrifugal policy). Menjadi pertanyaan
apakah memungkinkankah dalam situasi
mainstream uphoria semua ingin mekar saai
ini yang sangat kuat, kebijakan tentang
penggabungan dapat dilakukan ?.
Jawabannya ya, melalui policy instrument
yang merangsang atau paling tidak orang
lebih berpikir “lebih baik untuk tidak mekar
dari pada mekar”. Misalnya kebijakan berupa:
1) Memberikan insentif fiskal khusus
bagi daerah-daerah induk yang solid
dan agar tetap intake/solid.
2) Mendesian perencanaan
pembangunan yang masif pada
daerah solid/induk yang
mensyaratkan bahwa alokasi
anggaran/program pusat hanya
digulirkan pada daerah yang sifat
terotorialnya memiliki soliditas yang
baik atau berdasarkan syarat luas
wilayah tertentu dan fungsional
kawasan.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 18
3) Membuat efek jera untuk mekar
dengan negative policy.
4) Memberikan isentif fiskal yang lebih
besar melebihi APBD masing-masing
daerah secara parsial jika kedua
daerah tersebut digabung, dengan
logika jika daerah A=3, daerah B=2,
A+B=5, tapi jika A gabung B=10,
termasuk insentif pejabat/PNS dan
insentif nyata dan bermakna bagi
warganya.
c. Pilihan Kebijakan Konstanta yang Pro Aktif
(Cosntants/Static Policy)
Pilihan kebijakan Statis/Konstanta
plus kata aktif dimaksudkan bahwa
pemerintah melakukan moratorium
pemekaran secara berkelanjutan dan
superketat dengan policy instrument dalam
bentuk:
1) Redesain Sistem Pemilu di daerah dan
perluasan sistem kerja anggota DPRD yang
terpilih. Redesain Sistem pemilu mencakup
menambah jmlah anggota DPRD secara
rasional, penambahan dapil dalam wilayah
yang lebih kecil dengan jumlah daftar calon
sementara (DCS) yang ditingkatkan. Perluasan
Sistem kerja DPRD, adalah adanya kantor
perwakilan masing-masing DPRD di
Kabupaten/Kecamatan yang mana
mewajibkan anggota DPRD bersangkutan
berkantor dan melayani masyarakatnya tanpa
menunggu jadwal reses dalam periode waktu
tertentu.
2) Rekruiment politik dan birokrasi
yang berbasis representative local people yang
bersifat afirmatif, adil dan memberdayakan.
3) Penataan kembali organisasi
pemerintahan daerah yang memungkinkan
adanya kembali kantor perwakilan
Gubernur/Bupati/Camat yang tugas dan
fungsinya lebih diperluas.
4) Defracted Government Facilties,
penyebarluasan fasiltas perkantoran utama
pemerintah dalam bentuk penempatan kantor
dinas yang disebar sesuai dengan kondisi dan
fungsi wilayahnya, sehingga kantor dinas
tidak harus semuanya menyatu di Ibukota
Pemerintahan, apalagi dengan zaman mobile
government sekarang soal jarak tidak lagi
menjadi hambatan dalam melakukan
komunikasi antara pejabat.
5) Kebijakan pembangunan yang harus
berkeadilan dan merata.
6) Pejabat publik yang harus lebih sering
turun ke bawah/blusukan secara terprogram
dan cepat saat darurat tetapi bukan sekedar
pencitraan.
7) Membangun nilai-nilai yang
memperkuat ikatan kebersamaan, kesamaan
dan kebanggan teritorial dalam bingkai
NKRI.
8) Mengatur secara ketat agar Isu
Pemekaran tidak menjadi amunisi dan
kanalisasi suara saat pemilu.
9) Mengembangkan kebijakan
Intermunicipal Cooperation (IMC), sebuah
kawasan pembangunannya dikeroyok
bersama oleh sesama pemerintah daerah, yang
apada gilirannya membantu meringankan
pembiayaan pembangunan dan sekaligus
melakukan pemerataan pembangunan.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 19
10) Dapat membetuk kembali badan
otoritas khusus kawasan yang pimpinan
otoritasnya ditunjuk langsung oleh
pemerintah tingkat atas.
D. Relevansi Desain Penataan Daerah dan
Proyeksi Peluang Pembentuk DOB Baru
di Sulawesi Tengah.
1. Relevansi Penataan Daerah
Walapun keberadaan Desain penataan
daerah diperintahkan oleh peraturan
perundang-undang, namun relevansinya
menjadi dipertanyakan dengan alasan sebagai
berikut.
a. Dalam teori sangat jarang mendesain
sebuah daerah yang didasarkan pada
perkiraan delianasi otonomi juridis
administratif yang ada adalah desai
fungsional kawasan, karena tidak pernah kita
dapat memperkirakan dan mengarahkan
evolusi sebuah daerah termasuk negara harus
terdiri dari beberapa provinsi atau terdiri dari
beberapa kabupaten/kota. Yang seharusnya
diatur dalam desain penataan daerah adalah
syarat-syarat atau indikator yang
meneunjukan bahwa sebuah daerah untuk
alasan tertentu lebih baik ditetapkan sebagai
wilayah adminsitratif pemerintahan tersendiri.
b. Pada sisi lain dalam sebuah desain
penataan daerah yang telah mematok bahwa
Indonesia atau sebuah provinsi akan terdiri
dari sejumlah Provinsi atau Kabupaten, justru
memicu dan memacu mindset dan keinginan
untuk mekar dan kontraproduktif untuk
menciptakan kebijakan penggabungan
(centripetal territorial policy).
c. Dalam situasi tertentu pemekaran
daerah tidak harus berdasarkan perhitungan
rasionalitas teknokratis belaka, tetapi dalam
sistuasi tertentu tidak bisa dihindari lebih
berkaitan dengan variabel politik, psikologi
politik dan budaya.
2. Policy Plausible dan Peluang Pemekaran
Daerah di Sulawesi Tengah
Berdasarkan ulasan pada bagian (1) di
atas, menunjukan sulit memproyeksikan di
Sulawesi Tengah ini idealnya atau dalam
perkembangannya akan jadi berapa provinsi
atau Kabupaten/Kota. Yang dapat dilakukan
adalah melakukan prakiraan berdasarkan
data/fakta dan political dan policy streaming
yang ada, terlebih pemerintah pada tanggal 28
Agustus 2017 yang lalu melalui Dirjen Otda
mengatakan bahwa pemerintah dalam
menghadapi pemekaran daerah, memiliki 3
skenari yaitu: (1) Skenario Longgar, (2)
Skenario Sedang dan (3) Skenario Ketat.
Dalam skenario longgar ada 264 daerah
pemekaran meliputi, 23 provinsi, 192
kabupaten, dan 49 kota. Skenario sedang ada
202 daerah pemekaran meliputi, 12 provinsi,
113 kabupaten, dan 77 kota. Kemudian,
skenario ketat ada 101 daerah pemekaran,
meliputi 11 provinsi, 78 kabupaten, dan 12
kota. Dengan demikian secara umum dapat
dikatakan bahwa:
a. Usulan Pembentukan Kabupaten
Moutong dan Tomini Raya lebih berpeluang
untuk diwujudkan, karena dilihat dari
prosesnya kedua calon DOB tersebut sudah
disahkan menjadi DOB sebagai usul inisiatif
DPR-RI.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 20
b. Usulan Pembentukan Sulawesi Timur
akan mendapatkan peluang untuk diproses
lebih lanjut, karena usulan daerah tersebut
pada tingkat daerah sudah selesai. Yang
menjadi kendala adalah transisi regulasi yang
mengatur pemekaran.
c. Daerah-daerah yang secara nyata dan
faktual benar-benar karena alasan jarak
pelayanan dan atau karena pertimbangan
letak geografis berada pada posisi enclave
dengan bagian lainnya dalam satu wilayah
administrasi daerah otonom atau mempunyai
nilai strategis nasional dan keamanan dapat
memiliki peluang dipertimbangkan untuk
diproses/difasilitasi.
E. PENUTUP
Berbicara tentang penataan daerah
seyogya kita memandang pada dua sisi, yakni
sisi urgensi dan relevansi centripetal
territorial policy yang berkosekuensi untuk
melakukan upaya penggabungan sejumlah
daerah otonom, pada sisi lain berupa
centrifugal territorial policy yang berimplikasi
pada kebijakan pemekaraan daerah.
Berkaitan dengan upaya
pensejateraan rakyat, peningkatan kualitas
pelayanan publik dan memperkjokoh NKRI,
pemekeran maupun penggabungan sejatinya
hanya menjadi intrumen untuk itu, bukan
sebagai tujuan akhir. Olehnya itu salah satu
hal yang perlu kita lakukan adalah merubah
mindset kita tentang konsep dan orientasi
penataan daerah dan pemekaran daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Alesina, Alberto & Enrico Spolaore, The Size
Of Nations, MIT Press, 2003
Argama, Rizky, Pemberlakuan Otonomi
Daerah dan Fenomena Pemekaran
Wilayah di Indonesia, Makalah,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2005.
B.C.Smith.,Decentralization, The Territorial
Dimension of state, George Allen &
Urwin Ltd, London 1985
BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017
BPS Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka
2017
BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka
2017
BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka
2017
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka
2017
BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka
2017
Bryant, Coralie & G.White, Louise.,
Managemen Pembangunan Untuk
Negara berkembang,
Terjemahan:Rusyanto L.Simatupang,
LP3ES, Jakarta, 1989
Carson, Richard, T, How many Subdivisions ?,
University of California, 2003
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 21
Cheema, G.Sabhir, Institutional Dimensions of
Regional Development, Maruzen Asia,
Nagoya, Japan, 1980
Djaelangkara, Rizali, Strategi dan Proyeksi
Pemekaran Daerah di Sulawesi Tengah,
Makalah, Pemda Sulawesi Tengah,
2017.
Effendi, Sofian, Alternatif Kebijkansanaan
Perencanaan Administrasi, Suatu
Analisis Retrospektif dan Prospektif,
Seri Monograf, Edisi September 1989,
FISIPOL UGM, Yogyakarta, 1989
Ferrazzi,Gabriele, Internal Experiences in
Territorial Reform- Implication for
Indonesia, DRSP, Agustus 2007
Harmantyo, Djoko, Pemekaran Daerah dan
Konflik Keruangan, kebijakan Otonomi
Daerah dan Implementasinya di
Indonesia, Makara Sains, Vol. 11, No.1,
April 2007: 16-22
Keban, Yeremias T. Pembahasan Pemekaran
dan Penggabungan Daerah, USAID-
DRSP, 2007
Keban, Yeremias T, Indikator Kinerja
Pemerintah Daerah: Pendekatan
Manajemen dan Kebijakan, makalah,
Jurusan Administrasi Negara Fisipol
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
1995
Mulyawan, Rahman, Masyarakat, Wilayah
dan Pembangunan, Unpad Press,
Bandung, 2016
Nazara, Suahasil & Nurkholis, Ukuran
Optimal Pemerintahan di Indoensia:
Studi Kasus Pemekaran Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Era
Desentralisasi, Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Indoensia, Vo. VII, No.2,
2007,
O’Leary, Brendan, Analysing Partition:
Definition, Classification and
Explanation, Political Gegraphy, xx
(2007) 1-23
Perfecto L.Padilla, (ed)., Strengthening Local
Government Administration and
accelerating Local Development, The
Asia Foundation Philippines, Manila,
1992
Pratikno, Usulan Perubahan Kebijakan
Penataan Daerah, Policy Paper, USAID-
DRSP, February, 2008
Ratnawati, Tri, Pemekaran Daerah, Politik
Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
Retnaningsih, Ning dkk (ed), Dinamika Politik
Lokal di indonesia, Penataan Daerah
(Territorial Reform) dan Dinamikanya,
Percik, Salatiga, 2008.
Rondinelli, Dennis A., Applied Methods of
RegionalAnalysis, The Spatial
Dimensions of Development Policy,
Westview Special Study,Boulder and
London, 1985
Syarifuddin, Pelitian tentang Pemetaan Makna
Politik Pemekaran Daerah di Indoensia
Pasca Orde Baru, Jurusan Ilmu
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 22
Pemerintahan Universitas Lampung,
2009.
Swianiewicz, Pawel, Teritorial Fragmentation
As a problem, Consolidation As a
Solution ?, dalam Territorial
Consolidation Reform in Europe, First
published in 2010, by the Local
Government and Public Service Reform
Initiative, Open Society Institute–
Budapest, OSI/LGI, 2010
Swianiewicz, Pawel (ed) Consolidation or
Fragmentation? The Size of Local
Governmentsin Central and Eastern
Europe , First published in 2002 by
Local Government and Public Service
Reform Initiative, Open Society Institute
Budapest.
Tarigan, Ritonga, Perencanaan pembangunan
Wilayah, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta,
2005
Tarigan, Antonius, Dampak Pemekaran
Wilayah, Jurnal Perencanaan
Pembangunan, Edisi 01/Tahun
XVI/2010
Tiebout, C M (1956) “A Pure Theory of Local
Expenditure”, Journal of Political
Economy.
Trueblood and Beth Walter Honadle, An
Overview of Factors Affecting the Size
of Local Government, Staff Pape P94-7,
Departemen of Agricultural and
Applied Economics College of
Agriculture University Of Minosota,
April 1994.
Zhijian, Zhang & Raul P.De Gusman.,
Administrative Reform Toward
Promoting Productivity in Bureaucratic
Performance, Eropa, Manila, 1992
Bappenas dan UNDP, Studi Evaluasi
Pemekaran Daerah, July 2007,
Lembaga Administrasi Negara, Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Otonomi
Daerah untuk periode 1999-2003,
(laporan penelitian) Jakarta, 2005
Mabuchi, Masaru. Municipal Amalgamation
in Japan, World Bank, Washington, 2001
Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi
Daerah Departemen Dalam Negeri,
Efektifitas Pemekaran Wilayah Di Era
Otonomi Daerah,(laporan penelitian)
Jakarta 2005.
Reiljan, Janno & Aivo Ulper, The Necessity of
an Administrative-Territorial Reform in
a Country: The Case of Estonia, The
University of Tartu Faculty of Economic
and Bussiness Administration, 2010.
Syarifuddin, Pelitian tentang Pemetaan Makna
Politik Pemekaran Daerah di Indoensia
Pasca Orde Baru, Jurusan Ilmu
Pemerintahan Universitas Lampung,
2009.
Swianiewicz, Pawel, Teritorial Fragmentation
As a problem, Consolidation As a
Solution ?, dalam Territorial
Consolidation Reform in Europe, First
published in 2010, by the Local
Government and Public Service Reform
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 23
Initiative, Open Society Institute–
Budapest, OSI/LGI, 2010
USAID-DRSP-PERCIK, Proses dan Implikasi
Sosial Politik Pemekaran, Studi Kasus
Sambas dan Buton,
Usaid, Policy Implemntation Barriers
Analysis: Conceptual Framework and
Pilot Test in Three Countries, Healt
Policy Initiative, Oktober, Washington
DC, 2009
Wirabhumi, Edy, S. Pemberdayaan Hukum
Otonomi Daerah dan Potensi Wilayah:
Studi Tentang kemungkinan
Terbentuknya Provinsi Surakarta,
Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Diponegoro,
Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan
Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahyun 2008
Pedoman Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
tahun 2010 Tata Cara Pelaksanaan
Evaluasi Daerah Otonom Baru.
Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia,
2010-2025, Kemendagri, Juni 2010
Kontan.co.id, Dana Terbatas, pemerintah
tunda pemekaran daerah, Rabu, 19 Juli
2017.
Liputan6.com, JK: Moratorium Pemekaran
Daerah Masih Berlaku, Rabu, 19 Juli
2017.
http://www.beritapalu.com/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1097:
sulteng-dikembangan-jadi-13-
kabupaten&catid=34:palu&Itemid=126
http://news.liputan6.com/read/3074809/pe
merintah-siapkan-3-skenario-
pemekaran-daerah
http://www.mediaindonesia.com/index.php
/news/read/119897/pemerintah-
tunda-pemekaran-314-daerah/2017-08-
29, Pemerintah Tunda Pemekaran 314
Daerah
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 24
THE OPINION OF COMMUNICATION SCIENCE STUDENTS ON CYBERSTALKING PHENOMENON IN SOCIAL MEDIA
OPINI MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI TERHADAP FENOMENA CYBERSTALKING DI MEDIA SOSIAL
MUHAMAD ISA YUSAPUTRA1*, DYAH FITRIA KARTIKA SARI2, ROMAN R. UTAMA3,
ALDINA HUSNUZAN4
1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah *E-mail: [email protected]
Naskah diterima : 6 Mei 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
Cyberstalking behavior that leads to the attack of one's privacy area has not happened much in Indonesia but
does not rule out the possibility of seeing the percentage of Indonesian people as internet users constantly
increasing. This behavior can be compared to cyberbulliying but has more indications where the perpetrator
continues to follow victims in cyberspace to sometimes in the real world. Seeing this problem, this study
describes the opinions of students of communication science on cyberstalking behavior. By using uncertainty
reduction theory through three approaches strategies, namely passive strategies, active strategies and
interactive strategies associated with cyberstalking phenomena. Retrieval of data in this study uses a
questionnaire with the presentation of quantitative data, where the results of data processing are described.
Cyberstalking is an inevitable phenomenon of technological development, in a passive strategy in some cases
recognizing the nature and behavior of someone from social media, is not an easy thing to do. Active strategies
that involve communication with people around the target, can be done by searching for information through
social media, although to recognize the nature and behavior of a person is not easy, but finding information
about others on social media in the phenomenon of cyberstlaking is one of the steps interfere with the lives of
others. The process that has involved direct interaction with victims is an interactive strategy that has been
very disturbing to others. Cyberstalking which happens also lies behind many factors, it can be from yourself,
others, even the surrounding environment.
Keywords : Student Opinion, Cyberstalking, Social Media
Perilaku CyberStalking yang menjurus pada penyerangan wilayah privasi seseorang belum banyak terjadi di
Indonesia namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dengan melihat persentase masyarakat Indonesia
sebagai pengguna internet terus menerus bertambah. Perilaku ini bisa disetarakan dengan cyberbulliying
tetapi berindikasi lebih dimana pelaku terus menerus membuntuti korban di dunia maya hingga terkadang di
dunia nyata. Melihat permasalahn tersebut maka penelitian ini, menggambarkan opini mahasiswa ilmu
komunikasi terhadap perilaku cyberstalking. Dengan menggunakan teori pengurangan ketidakpastian melalui
tiga strategi pendekatan, yaitu strategi pasif, strategi aktif dan strategi interaktif yang dikaitkan dengan
fenomena cyberstalking. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket dengan penyajian data
kuantitatif, dimana hasil pengolahan data dideskripsikan. Cyberstalking merupakan fenomena yang tidak bisa
dielakkan dari perkembangan teknologi, pada strategi pasif dibeberapa kejadian mengenali sifat dan prilaku
seseorang dari sosial media, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Strategi aktif yang melibatkan komunikasi
dengan orang-orang disekitar target sasaran, dapat dilakukan dengan cara mencari informasi melalui sosial
media, walaupun untuk mengenali sifat dan perilaku seseorang tidak mudah, namun mencari informasi
tentang orang lain di sosial media dalam fenomena cyberstlaking menjadi salah satu untuk langkah
menginterfensi kehidupan orang lain. Proses yang sudah melibatkan interaksi langsung dengan korban,
merupakan strategi interaktif yang sudah sangat mengganggu orang lain. Cyberstalking yang tejadi juga
dilatara belakangi oleh banyak faktor, bisa dari diri sendiri, orang lain bahkan lingkungan disekitarnya.
Kata Kunci : opini mahasiswa, cyberstalking, media sosial
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 25
A. PENDAHULUAN
Internet menjadi kata yang telah lekat
dibenak hampir semua masyarakat dunia.
Penggunanya dari tahun ketahun yang terus
mengalami peningkatan yang cukup drastis.
Data pengguna internet dunia menunjukkan
bahwa asia memiliki pengguna terbanyak di
bandingkan benua lain di dunia seperti
terlihat pada gambar grafik di bawah ini.
Indonesia menjadi pengguna terbanyak ke
enam di dunia (https://kominfo.go.id/)
Media sosial menjadi bagian yang tidak bisa di
pisahkan dari kehidupan masyarakat
Indonesia. Keberadaan media baru, menjadi
barometer dari berkembangnya teknologi
komunikasi. Media baru dan media lama
menjadi satu bahasan yang sering
diperbincangkan, bukan lagi mengenai media
cetak dan elektronik, lebih dari itu media baru
menjadi implementasi media dengan jaringan
internet. Rianto Puji (2016:91) menjelaskan
para penyedia content media baru, dalam
beberapa hal, tidak terikat pada sistem kerja
semacam itu. Ketika seseorang dapat
berperan sebagai produsen pesan dan
penerima pesan dalam waktu yang hampir
bersamaan, standart profesional dengan
sendirinya ‘lenyap’. Khayak bisa terjerat
dalam informasi-informasi yang tidak akurat
sebagaimana standart yang biasa menjadi
acuan media konvensional.
Fenomena-fenomena yang kemudian hadir
dari lahirnya media baru dan juga media
sosial sebagai media komunikasi yang banyak
disalahgunakan oleh pengguna internet
khususnya media sosial adalah merugikan
dan mengganggu kenyamanan orang lain.
Aktivitas pengguna remaja berselancar di
dunia maya seiiring dengan semakin
beragamnya media baru yang dapat memuat
seluruh aktivitas keseharian mereka.
Kedekatan remaja dengan dunia maya
menjadi bagian yang tidak terpisahkan .
Perilaku penyimpangan pun mulai
bermunculan seiring Hal tersebut paling
rentan dialami oleh remaja yang
memanfaatkan media sosial sebagai bentuk
mengeksistensikan diri di media sosial. Bocij
(2002). Perilaku CyberStalking yang menjurus
pada penyerangan wilayah privasi seseorang
belum banyak terjadi di Indonesia namun
tidak bisa dipungkiri melihat jumlah
pengguna internet di Indonesia yang terus
menerus bertambah. Perilaku ini bisa
disetarakan dengan cyberbulliying namun
berindikasi lebih dimana pelaku terus
menerus membuntuti korban di dunia maya
hingga terkadang di dunia nyata. Remaja lebih
retan terhadap perilaku ini berdasarkan
prilaku mereka yang begitu mudah
membagikan hal privasi ke dalam media baru.
Mahasiswa ilmu komunikasi yang berada
pada kisaran umur usia remaja. Sebagai
remaja dengan pengetahuan bidang ilmu
komunikasi tentunya memiliki opini terhadap
perilaku cyberstalking yang dikelompokkan
sebagai kejahatan cyber. Berdasarkan hal
tersebut maka penelitian ini hendak
menggambarkan mengenai opini mahasiswa
ilmu komunikasi terhadap prilaku
cyberstalking.
B. LANDASAN TEORI
Konsep Komunikasi Antar Pribadi
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 26
Pendekatan dengan komunikasi antar
pribadi dinilai mampu dalam menjalin
hubungan yang lebih intens dan
berkelanjutan, namun untuk mencapai level
dimana hubungan atntar pribadi akan menjadi
lebih intens, tergantung dari kebutuhan.
William Schutz (1966) seorang psikolog yang
mengembangkan teori kebutuhan antar
pribadi seperti yang dikutip Wood (2013:12-
13) menegaskan bahwasanya hubungan antar
pribadi akan berkelanjutan tergantung dari
tiga kebutuhan dasar. Kebutuhan yang
pertama adalah kebutuhan afeksi kebutuhan
ini adalah kebutuhan dimana adanya
keinginan untuk memberi serta mendapatkan
kasih sayang. Kedua adalah inklusi, dimana
adanya keinginan untuk menjadi bagian dari
kelompok sosial tertentu. Dan ketiga adalah
control, kebutuhan dimana seseorang ingin
mempengaruhi orang lain atau peristiwa
dalam kehidupan orang lain tersebut.
Perkembangan hubungan dalam
komunikasi antarpibadi, memberikan
gambaran tentang keakraban dalam
hubungan. Dalam komunikasi diadik
keakraban dalam hubungan menjadi bagian
penilaian kualitas hubungan. Waring dan
rekan-rekannya (1980) menemukan lima
kategori respons, dimana orang-orang
mengaitkan keakraban dengan berbagai
pikiran, keyakinan, fantasi, minat, cita-cita dan
latar belakang. Selain itu, seksualitas tidak
menjadi bagian dari definisi keakraban,
menurutnya, hubungan keakraban tidak
memerlukan seksualitas (Zakiah, 2002:299).
Hubungan yang semakin akrab merupakan
indikato dalam perkembangan hubungan.
Pada tahap hubungan yang semakin akrab,
ada keyakinan yang hadir antara masing-
masing anggota ynag terblibat dalam
hubungan akan keberlangsungan dan harapan
atas hubungan yang dijalani. Hubungan yang
terjadi dalam komunikasi antar pribadi sangat
dipengaruhi oleh persepsi yang dibangun dari
masing-masing individu.
Liliweri (2011:157) menjelaskan bahwa
persepsi sendiri merupakan suatu proses
dimana individu lebih menyadari tentang
objek ataupun peristiwa yang terjadi dalam
dunia. Lebih lanjut Liliweri mengemukakan
lima tahapan utama dalam proses ini yaitu
stimulation, organization, interpretation-
evaluation, memory dan recall. Komunikasi
antarpribadi yang dilakukan haruslah efektif,
agar dapat menegetahui secara langsung
tanggapan yang diberikan oleh orang lain
terkait dengan informasi yang kita berikan
tentang diri kita dan masalah yang dihadapi.
Menurut De Vito (dalam Liliweri, 2003: 55)
menjelaskan tentang pengertian komunikasi
antar pribadi yang berbeda dengan bentuk
komunikasi lainnya, dalam komunikasi antar
pribadi anggota yang terlibat baik secara
jumlah dan orang-orang yang terlibat
(interectants). Dalam komunikasi antar
pribadi kedekatan fisik dan jaringan antara
anggota yang terlibat dalam komunikasi
sangat dekat dan tanggapan baliknya sangat
cepat.
Menjalin komunikasi dan hubungan
dengan orang lain dalam ranah komunikasi
antar pribadi, melahirkan teori-teori yang
mengupas tentang komunikasi antar pribadi.
banyak hal yang bisa kita lakukan dalam
upaya mengurangi ketidakpastian dalam
penerimaan dan pemaknaan informasi, sala
satu cara untuk melakukannya adalah dengan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 27
mengurangi kesenjangan ketidakpastian yang
terjadi antara orang-orang yang terlibatsuatu
percakapan. Salah satu teori yang dibahas
konteks komunikasi antar pribadi adalah teori
pengurangan ketidakpastian dimana masing-
masing individu yang terlibat dalam
komunikasi berusaha untuk mengetahui hal-
hal berupa informasi tentang lawan bicara
mereka.
Uncertainty Reduction Theory (Teori
Pengurangan Ketidakpastian)
Teori pengurangan ketidakpastian
(Uncertainty Reduction Theory) merupakan
teori yang menjelaskan proses awal
bagaimana mengenal dan menjalani
hubungan dengan orang lain (LittleJohn,
2009:256). Saat ini, ketika kita akan memulai
hubungan atau perkenalan dengan orang lain,
seringkali kita mencari tahu tentang
karakteristik ataupun apa saja yang
berhubungan dengan orang tersebut. Berger
(LittleJohn, 2009:257) menyatakan bahwa
manusia seringkali kesulitan dengan
ketidakpastian, mereka ingin dapat menebak
prilaku, sehingga mereka terdorong untuk
mencari informasi tentang orang lain.
Sebenarnya pada teori pengurangan
ketidakpastian ini, adalah dimensi dasar
dalam pengembangan suatu hubungan.
Komunikasi sekarang ini, tidak lagi hanya
berada dalam ranah dan dimensi yang sama.
Teori ini adalah bagian dari komunikasi
interpersonal yang terjadi pada dua orang
yang bertemu untuk pertama kali. Mereka
yang bertemu untuk pertama kalinya dan
akan memulai suatu hubungan melalui
sebuah percakapan akan menghadirkan
penilaian yang subjektif terhadap lawan
bicaranya.
Adanya ketidak pastian dan juga
timbulnya hal-hal yang menjadi pertanyaan
serta melahirkan dugaan-dugaan baik yang
positif maupun yang negatif. Atas dasar
tersebut tercetusnya Teori Pengurangan
Ketidakpastian ( Uncertainty Reduction
Theory) karya Charles Berger dan Richard
Calabrese. Komunikasi merupakan perantara
yang dipakai untuk meminimalisir
ketidakpastian yang muncul. Dimana
komunikasi dijadikan ukuran untuk
meminimalisir adanya ketidakpastian yang
hadir dalam percakapan. Teori reduksi
ketidakpastian atau Uncertainty Reduction
Theory disingkat URT mencari penjelasan
bagaimana berkomunikasi apabila tidak
memperoleh kepastian tentang lingkungan-
lingkungan sekitar. (Budyatna, Muhammad
2015). Teori ini menyoroti ketidakpastian
sebagai kekuatan kausal membentuk perilaku
komunikasi dan meningkatkan prediksi-
prediksinya yang dapat diukur tentang
bagaimana orang berperilaku apabila mereka
merasa tidak pasti. URT memulai dengan
dasar pikiran bahwa orang termotivasi untuk
mengurangi ketidakpastian tentang
lingkungan sosial, teori ini berpendapat
bahwasanya individu-individu berusaha
untuk memprediksi dan menjalankan
lingkungan-lingkungan mereka. URT
menggunakan teori informasi untuk
mendefinisikan ketidakpastian sebagai fungsi
tentang jumlah dan kemungkinan mengenai
alternatif yang mungkin terjadi. Berger
(LittleJohn, 2009:257-259) mengidentifikasi tiga
strategi yang orang gunakan untuk
menanggulangi ketidakpastian untuk
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 28
mendapatkan informasi mengenai diri sendiri
dan orang lain, yaitu :
a. Strategi pasif Strategi pasif meliputi
mengamati orang yang menjadi target
dari kejauhan. strategi pasif meliputi
reactivity searching dan disinhibition
searching. Reactivity searching berupa
mengamati seseorang ketika dia sedang
melakukan sesuatu atau mengamati
bagaimana reaksinya pada situasi
tertentu. Disinhibition searching berupa
mengamati seseorang dalam situasi
informal dimana dia dalam keadaan
santai tidak terlalu menjaga penampilan
dan berperilaku apa adanya.
b. Strategi akif Strategi aktif terjadi
apabila individu-individu mengambil
tindakan untuk memperoleh informasi
dan tidak benar-benar berinteraksi
dengan orang yang menjadi target,
yaitu dengan menanyakan orang lain
tentang orang yang menjadi target.
c. Strategi Interaktif Strategi interaktif
memerlukan berkomunikasi dengan
orang yang menjadi target. Strategi ini
awalnya dari tanya jawab sehinga
memperoleh wawasan atau pengertian
dan menemukan kesamaan-kesamaan,
tetapi norma-norma kesopanan
membatasi jumlah dan ketegasan
pertanyaan-pertanyaan yang pantas.
Kedua adalah mencari pengungkapan
secara timbal balik. Ketiga adalah
membuat target rileks dengan suasana
santai yang memungkinkan besar
individu dalam keadaan
mengungkapkan informasi tentang diri
mereka.
C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif
adalah penelitian yang berlandasan pada
filsafat positivisme, yang digunakan untuk
meneliti yang berfokus pada populasi dan
sampel tertentu, untuk teknik pengambilan
sampel biasanya dilaksanakan secara random
(Sugiyono, 2013:13). Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif dalam
mengemukakan fenomena-fenomena yang
ada di masyarakat. Fenomena yang terjadi
bisa dalam bentuk, aktivitas, karakteristik,
perubahan, hubungan, dan kesamaan, serta
perbedaan antara fenomena yang hadir
dengan fenomena lainnya (Sukmadinata,
2006:72). Tradisi kuantitatif sebagai instrumen
yang digunakan telah ditentukan sebelumnya
dan tertata dengan baik sehingga tidak banyak
memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan
imajinatif dan refleksitas. Dalam penelitian ini,
Instrumen yang biasa digunakan adalah
angket (kuesioner) (Mulyadi, 2011:131).
Penelitian ini dilakukan di program studi
ilmu komunikasi kampus Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako,
Kampus Bumi Tadulako Jalan. Soekarno Hatta
Kelurahan Tondo Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Populasi adalah keseluruhan objek yang
berupa manusia, hewan, tumbuh- tumbuhan,
udara, gejala-gejala, nilai test, peristiwa-
peristiwa dan sebagainya sebagai sumber data
yang memiliki karakteristik tertentu dalam
suatu penelitian (Bungin, 2001:99). Populasi
pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 29
komunikasi Universitas Tadulako Angkatan
2015 yakni sejumlah 136 orang. Sampel adalah
sebagian dari keseluruhan berupa objek atau
fenomena yang akan menjadi fokus
pengamatan (Kriyantono , 2010:153).
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan
berdasarkan area yakni mengambil
mahasiswa angkatan 2015 yang masih aktif
berkuliah di program studi ilmu komunikasi
Universitas Tadulako. Disebabkan populasi
yang banyak dan tidak mungkin untuk
diambil semua maka jumlah penentuan
sampel dalam penelitian ini didasarkan
kepada pendapat Suharsini Arikunto yang
mengatakan “Untuk mengetahui sekedar
ancar-ancar maka apabila populasi kurang
dari 100 orang maka lebih baik diambil semua,
sehingga penelitian itu merupakan penelitian
populasi. Jika jumlah subjeknya lebih dari 100
orang, maka dapat diambil 5 persen atau 20
sampai dengan 25 persen atau lebih”
(Arikunto, 1998:120). Berdasarkan ketentuan
tersebut di atas maka peneliti menetapkan
sampel sebesar 25 persen dari jumlah 138
populasi, maka sampel dari penelitian ini
adalah berjumlah 35 responden.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Strategi Pasif
Opini mahasiswa terkait strategi pasif
yang biasanya dilakukan oleh pelaku
cyberstalking dalam mempengaruhi target
sasarannya. Pada strategi pasif ada lima
pertanyaan yang diajukan kepada responden.
Secara umum terkait dengan strategi pasif
yang mungkin dilakukan oleh pelaku
cyberstalking. 71,4% mahasisiwa mengatakan
setuju sering melihat orang-orang mencari
tahu informasi melalui sosial media melalui
interaksinya kepada orang lain. Pencarian
informasi secara terus-menerus tentang suatau
objek yang menjadi sasaran dan sudah
mengganggu privasi orang lain sudah
termasuk kepada tindakan cyberstalking.
Berkaitan dengan teori pengurangan
ketidakpastian yang menyoroti ketidakpastian
sebagai kekuatan kausal membentuk perilaku
komunikasi dan meningkatkan prediksi-
prediksinya yang dapat diukur tentang
bagaimana orang berperilaku apabila mereka
merasa tidak pasti. URT memulai dengan
dasar pikiran bahwa orang termotivasi untuk
mengurangi ketidakpastian tentang
lingkungan sosial, teori ini berpendapat
bahwa individu-individu berusaha untuk
memprediksi dan menjalankan lingkungan-
lingkungan mereka.
URT menggunakan teori informasi
untuk mendefinisikan ketidakpastian sebagai
fungsi tentang jumlah dan kemungkinan
mengenai alternatif yang mungkin terjadi
(Budyatna, Muhammad 2015). Sosial media
menjadi bagian dari medium untuk
memperoleh banyak informasi tanpa harus
melibatkan objek informasi secara langsung.
Melalui sosial media banyak informasi yang
akan diperoleh mengenai seseorang yang akan
membuat seseorang mengenali orang lain
tanpa harus berinteraksi langsung. Lebih
mudah mencari informasi mengenai sifat dan
prilaku seseorang di sosial media melalui
komentar dan postingan-postingan, merupaan
pernyataan yang tenyata 34,3% mahasisiwa
menilai kurang setuju terhadap pernyataan
tersebut. dapat disimpulkan bagi responden
yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor,
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 30
tempat tinggal dan interaksi sosial dalam
masyarakatpun mempengaruhi opini
mahasiswa yang menyatakan kurang setuju
mencari informasi tentang sifat dan prilaku
seseorang lewat sosial media lebih mudah.
Jawaban yang berbanding terbalik dengan
pernyataan yang menyatakan Cyberstalking
menjadi suatu hal yang biasa di dunia maya
saat ini, 51,4% menjawab setuju dengan
pernyataan tersebut dan 42,9% menjawab
sangat setuju. Sering memperlihatkan aktifitas
melalui sosial media merupakan salah satu
cara pelaku cyberstalking mengetahui sifat
dan karakteristik korbannya. Responden
ternyata kurang setuju dengan
memperlihatkan aktifitas mereka di sosial
media sebesar 48,6% responden menjawab
kurang setuju untuk memperlihatkan aktifitas-
aktifitas keseharian meeka di sosial media.
2. Strategi Aktif
Strategi aktif dalam kaitanya dengan
fenomena cyberstalking merupakan langkah
yang dilakukan oleh cyberstalker dengan
melakukan pengamatan dan juga komunikasi
untuk memperoleh informasi-informasi
mengenai target sasaran melalui orang lain,
mengenali sifat dan prilaku target sasaran
melalui sosial media.
Dalam strategi ini, cyberstalker tidak
hanya mengamati target sasaran tetapi juga
mengganggu pribadi target melalui informasi-
informasi yang diperoleh dari orang lain. Pada
teori pengurangan ketidakpastian, komunikan
dan komunikator yang terlibat dalam
hubungan, akan berusaha untuk mencari tahu
lebih detail tentang informasi-informasi
mengenai orang lain tersebut. Strategi aktif
dalam cyberstalking dimana pelaku berusaha
untuk mencari informasi mengenai korban
melalui hal-hal disekitarnya, misalnya dari
interaksinya dengan orang lain dan juga
responnya terhadap suatu hal. Pada
pernyataan tentang menanyakan informasi
melalui orang lain dapat dibenarkan,
responden membenarkan hal tersebut dengan
persentase 48,6% setuju terhadap pernyataan
tersebut. dapat disimpulkan bahwa opini
responden membenarkan jika ingin
mengetahui informasi tentang seseorang bisa
melalui orang lain.
Sering mencari informasi tentang
seseorang melalui sosial media adalah hal
yang biasa terjadi, pernyataan tersebut
dijawab dengan 62,9% responden yang
menjawab setuju mencari informasi dari sosial
media merupakan hal yang biasa terjadi saat
ini. Sosial media membantu orang untuk
mencari tau informasi tentang orang lain
tanpa berinteraksi secara langsung.memahami
bahwa teknologi bisa dimanfaatkan dengan
baik dan bijak dan 68,6 persen responden
menjawab setuju bahwa kemudahan yang
dihasilkan oleh sosial media adalah dapat
dimanfaatkan untuk mencarai dan
memperoleh informasi tentang seseorang
tanpa harus melakukan komunikasi dan
interaksi dengan orang yang bersangkutan.
Pemahaman responden mengenai pelaku
cyberstalking dinilai baik dengang jumlah
persentase yang mnejawab pernyataan,
Cyberstalking bisa dilakukan oleh siapa saja di
sosial media sebesar 45,7% responden
menjawab sangat setuju dnegan pernyataan
tersebut dan 45,7% lainnya responden
menjawab setuju. Dari jawaban responden
dapat diketahui bahwa responden sudah
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 31
memahami cyberstalking bisa dilakukan oleh
siapa saja dan korbannya bisa siapa saja.
Mengingat hal tersebut bisa saja terjadi pada
siapa saja, membatasi diri untuk tidak
memperlihatkan dan membagi hal- hal pribadi
ke sosial media menjadi salah satu langkah
penangnan untuk mengurangi resiko menjadi
korban dari pelaku cyberstalking.
3. Strategi Interaktif
Cyberstalking menjadi fenomena yang
merugikan masyarakat saat ini. 42,9%
responden menyatakan kurang setuju
terhadap pernytaan tersebut. Bagi responden,
cyberstalking bukanlah hal yang dapat
merugikan masyarakat. Dalam sebuah
penelitian mengenai Cyberbullying and Self
Esteem dijelaskan bahwa para remaja yang
melakukan cyberbullying merupakan remaja
yang memiliki kepribadian otoriter dan
kebutuhan yang kuat untuk menguasai dan
mengendalikan orang lain (Patchin & Hinduja,
2010). Fenomena cyberstalking yang menjadi
marak saat ini, memberikan peluang bagi
pelaku untuk melakukan kejahatan pada siapa
saja. Fenomena ini juga bisa saja terjadi di
sekitar kita, sehingga tidak menutup
kemungkinan orang- orang disekitar kita
pernah menjadi korban cyberstalking. Hal ini
juga dikemukakan oleh responden yang
menjawab pernah melihat orang-orang yang
menjadi korban Cyberstalking 57,1% dengan
jawaban setuju atas pernyataan tersebut. Hal
tersebut berbanding terbalik dengan
pernyataan yang menyatakan “ menurut saya
cyberstalking sudah sangat mengganggu jika
sudah terjalin interaksi ” , sebesar 40,0%
responden menjawab kurang setuju dengan
pernyataan tersebut. Hal tersebut
menggambarkan bahwa menurut responden
cyberstalking tidak begitu membahayakan
dan dinilai belum sampai mengganggu jika
sudah terjadi komunikasi antara pelaku dan
korban.
Pernyataan yang menyatakan bahwa
cyberstalking merupakan sikap yang negatif
yang dilakukan karena sudah menganggu
privasi seseorang, sebesar 34,3% responden
menjawab setuju dengan pernyataan tersebut
dan 31,1% menjawab kurang setuju atas
pernyataan tersebut. hal ini menggambarkan
bahwa bagi responden cyberstalking yang
sudah mengganggu privasi orang bukanlah
hal yang perlu dikhawatirkan. Beberapa
negara fenomena cyberstalking menjadi
bentuk kejahatan yang juga ditakuiti dan
selalu diwaspadai. Beberapa kasus
cyberstalking yang sudah mengancam
keselamatan orang lain menjadi perhatian
tersendiri. Cyberstalking, yang melibatkan
perilaku yang berulang-ulang dan tidak
diinginkan menyebabkan ketakutan pada
target atau korban dari cyberstalker, kejahatan
ini sudah terjadi dan diakui di lebih dari 50
negara sebagai kejahatan yang merugikan
orang lain (https://programs
.online.utica.edu/) Banyak faktor yang
melatar belakangi seseorang untuk melakukan
cyberstalking terhadap orang lain. Fakor
dendam, iri hati dan sakit hati menjadi
beberapa fakto diantaranya selian faktor
eksistensi dan juga main-main. Dalam
pernyataan “Menurut saya melakukan
cyberstalking karena adanya dendam dan iri
hati dimana adanya semangat ingin
menguasai korban dengan kekuatan fisik dan
meningkatkan popularitas pelaku dikalangan
teman sepermainan” sebanyak 37,1%
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 32
resonden menjawab kurang setuju atas
pernayataan tersebut. hal ini dapat
menyimpulkan bahwa sebagian pandangan
responden menilai melakukan cyberstalking
untuk kepentingan popularitas dan
pengakuan bukan hal yang mutlak harus
dilakuakn ketika ada rasa dendam.
E. KESIMPULAN
Penelitian yang dilakukan dikalangan
mahasisiwa Ilmu Komunikasi FISIP Untad,
memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Cyberstalking merupakan fenomena
yang menjadi bagian dari perkembangan
teknologi, pada strategi pasif dibeberapa
kejadian bahwa mengenali sifat dan
prilaku seseorang dari sosial media,
bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut
yang tergambar dari opini mahasiswa ilmu
komunikasi Fisip Untad.
2. Strategi aktif yang melibatkan
komunikasi dengan orang-orang disekitar
target sasaran, dapat dilakukan dengan
cara mencari informasi melalui sosial
media, walaupun untuk mengenali sifat
dan perilaku seseorang tidak mudah,
namun mencari informasi tentang orang
lain di sosial media dalam fenomena
cyberstlaking merupakan salah satu
langkah menginterfensi kehidupan orang
lain.
3. Proses yang sudah melibatkan interaksi
langsung dengan korban, merupakan
strategi interaktif yang sudah sangat
mengganggu orang lain. Cyberstalking
yang tejadi juga dilatara belakangi oleh
banyak faktor, bisa dari diri sendiri, orang
lain bahkan lingkungan disekitarnya.
Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: PT. Rineka Cipta
Bagdakian, Ben H. 2004. The New Media
Monopoly. Boston:Beacon Press
Budyatna, Muhammad.2015. Teori-Teori
Komunikasi Antar Pribadi. Jakarta:
Kencana
Bungin, Burhan.2001.Metodologi Penelitian
Kualitatif Dan Kuantitatif.
Yogyakarta:Gajah Mada Press.
DeVito. 2001. The Interpersonal
Communication Book. New York:
Addison Wesley Longman.
DeVito.2003. Human Communication. 9th ed.
USA:Pearson education inc.
Effendy, Onong Uchjana. 2009. Ilmu
Komunikasi Teori dan Praktek.
Bandung:Remaja Rosdakarya
http://abduljalil.web.ugm.ac.id/2015/02/12/
cyberbullying/
http://ilkom.fisip.untad.ac.id/profil/sejarah/
https://fantasynight69.wordpress.com/2013/
04/29/kasus-cyberstalking-2/
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 33
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/p
engguna-internet-indonesia-nomor-
enam-dunia/0/sorotan_media
https://programs.online.utica.edu/articles/cy
berstalking Cyberstalking 101 oleh Gal
Shpantzer (diakses pada tanggal 03 juni
2018)
https://www.hidayatullah.com/berita/nasio
nal/read/2013/02/18/65860/kemenko
minfo-waspadai-sisi-negatif-teknologi-
informasi.html
INTERNET Abdul Rosid, ST PROGRAM
STUDI S1 MANAJEMEN STIE ADHY
NIAGA – BEKASI
Kerlinger, Alfred N. 2006. Asas-Asas
Penelitian Behavioral (Terjemahan).
Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press.
Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis
Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana.
Prenada Media Group
Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis
Riset Komunikasi: Disertai Contoh
Praktis Riset Media, Public Relation,
Advertising, Komunikasi Organisaso,
Komunikasi Pemasaran. Jakarta:
Kencana
Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba
Makna. Jakarta: Prenada media grup.
Littlejohn, Stephen dan Karen A Foss. 2009.
Teori Komunikasi. Penerjemah:
Mohammad Yusuf Hamdan. Jakarta:
Salemba Humanika
Margono. 2004. Metodologi Penelitian
Pendidikan.Jakarta: RinekaCipta
Mondry.2008. Pemahaman Teori Dan Praktek
Jurnalistik. Bogor:Ghalia Indonesia
Muyadi, Mohammad. 2011. Penelitian
Kuantitatif Dan Kualitatif Serta
Pemikiran Dasar Menggabungkannya.
Jurnal Study Komunikasi dan media.
Vol 15. No1.
Nasrullah. 2012. Komunikasi Antar Budaya Di
Era Budaya Cyber. Jakarta:Kencana
Media
Ruben, Brent, D dan Lea P. Stewart. 1998.
Communication and Human Behavior.
USA: Allyn & Bacon
Soedarsono, Dewi.2009.System Manajemen
Komunikasi, Teori,Model, Dan Aplikasi.
Bandung: simbiosa rekatama media
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Syaibani, Yunus Ahmad.2011. New Media,
Teori Dan Aplikasi. Surakarta:Lindu
Pustaka
West, Richard dan Lynn Turner. 2010.
Introducing Communication Theory
(analysis and aplication). Fourth
Edition. New York:MCGraw-Hill.
Wood.2000. Communication theory in action.
2nd ed. Printed in United States of
America.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 34
THE ROLE OF THE PALU CITY PUBLIC RELATION OFFICERS IN THE FESTIVAL PALU NOMONI IN MAINTAINING IMAGE OF PALU CITY
PERANAN HUMAS PEMDA KOTA PALU PADA EVENT FESTIVAL PESONA PALU NOMONI DALAM MENJAGA CITRA KOTA PALU
ALDIMAS D. SAMPOERNO1
1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako E-mail: [email protected]
Naskah diterima : 25 Mei 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
Palu City at the Palu Nomoni Festival event in maintaining the image of Palu City.The Palu Nomoni Festival
Event has been held in two editions in 2016 and 2017 in Palu City. In those two editions things were still found
which were feared to damage the image of Palu City as the host of the event. How does government public
relations play a role in maintaining the image of Palu City at the event. The type of research that will be used in
this research is qualitative descriptive research, namely research that aims to make a systematic, factual and
accurate description that describes the events that occur in the field, related to the role of the local government
of Palu City at the Palu Nomoni Festival event. The subjects of this study were 4 (four) informants with the
consideration that the appointed informants were representatives who could provide accurate information in
accordance with the needs and objects of the study. There are 4 (Four) roles of public relations according to
Dozier and Broom which are key research theories The results of the study show that out of the 4 (Four)
theories of public relations roles only 2 (two) are run quite well so that it can be said that public relations
efforts in maintaining the image of Palu City regarding the image of the Palu Nomoni Festival have not been
optimal.
Keywords : PR role, Palu Nomoni, image
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peranan humas pemda Kota Palu pada event
Festival Pesona Palu Nomoni dalam menjaga citra Kota Palu. Event Festival Pesona Palu Nomoni telah
diselenggarakan sebanyak dua edisi pada 2016 dan 2017 di Kota Palu. Dalam dua edisi tersebut masih
ditemukan hal-hal yang ditakutkan merusak citra Kota Palu selaku tuan rumah acara. Bagaimana humas
pemerintah berperan dalam menjaga citra Kota Palu pada event tersebut. Tipe penelitian yang akan digunakan
dalam penelitan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat
deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan, terkait
dengan peranan humas pemda Kota Palu pada event Festival Pesona Palu Nomoni dalam menjaga citra Kota
Palu. Subjek penelitian ini ialah 4 (Empat) orang informan dengan pertimbangan bahwa informan yang
ditunjuk adalah representatif yang dapat memberikan informasi akurat sesuai dengan kebutuhan dan objek
penelitian. Terdapat 4 (Empat) peranan humas menurut Dozier dan Broom yang menjadi teori kunci
penelitian. Adapun hasil penelitian ditunjukkan bahwa dari 4 (Empat) teori peranan humas hanya 2 (dua)
yang dijalankan dengan cukup baik sehingga dapat dikatakan bahwa upaya humas dalam menjaga citra Kota
Palu terkait event Festival Pesona Palu Nomoni belum maksimal.
Kata Kunci : Peran Humas, Palu Nomoni, Citra
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 35
A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara
dengan berbagai macam ragam budaya yang
unik, khas dan dinilai memiliki daya tarik
tersendiri yang membuat banyak orang
kagum serta takjub dengan banyaknya varian
budaya tersebut. Indonesia memiliki kekayaan
alam yang berlimpah, begitupun dengan adat
istiadatnya. Kebhinekaan yang dimiliki
Indonesia menciptaakan keragaman suku,
budaya, dan bahasa. Setiap daerah memiliki
kekayaannya masing-masing. Sampai dengan
November 2017, Indonesia tercatat memiliki
35 provinsi yang secara resmi berada dalam
naungan pemerintaan Republik Indonesia.
Masing-masing provinsi tersebut memiliki ciri
khas kebiasaan dan budaya yang berbeda-
beda, dari hal paling mendasar seperti bahasa
misalnya, Indonesia adalah negara yang
memiliki bahasa daerah yang cukup banyak,
di tiap provinsi memiliki bahasa daerahnya
masing-masing.
Sebagai contoh, di Pulau Jawa terdapat
beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur, uniknya meskipun
ke tiga Provinsi tersebut sama-sama terletak di
Pulau Jawa, namun ketiganya memiliki bahasa
daerahnya masing-masing. Itu jika kita hanya
membahas masalah bahasa, di Indonesia
masih ada sangat banyak budaya-budaya
yang menarik untuk dibicarakan. Budaya adat
istiadat, perilaku-perilaku, bahasa verbal dan
nonverbal, kuliner atau masakan hingga
karya-karya seni; seperti tarian, nyanyian,
peninggalan-peninggalan sejarah seperti
rumah adat dan lain-lain yang sangat banyak
jumlahnya. Hal inilah yang menjadi salah satu
bukti akan kekayaan negeri Republik
Indonesia.
Kota Palu adalah Ibukota Provinsi
Sulawesi Tengah yang memiliki varian
budaya dan pariwisata yang beraneka ragam,
khas dan menarik untuk diketahui. Mulai dari
suku, bahasa, pakaian adat tradisional, rumah
adat, tarian-tarian, senjata tradisional, lagu-
lagu daerah dan hal lainnya yang memiliki
nilai sentimental yang kuat. Ada berbagai
macam cara yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan citra suatu daerah. Misalnya,
pemerintah membuat kegiatan yang
bertemakan budaya dan kearifan lokal.
Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan
seperti ini, tentu secara otomatis seluruh pihak
yang terlibat turut mendeklarasikan budaya
kepada dunia. Kegiatan-kegiatan tersebut juga
bisa menjadi sarana promosi kepada
masyarakat luas terkait ragam budaya dan
keunikan serta ciri khas daerah masing-
masing. Hal ini semakin didukung dengan era
digital di mana semua hal bisa diliput,
diberitakan dan disebar luaskan sehingga
infomasinya bisa sampai kepada siapa saja
dan di mana saja.
Festival Pesona Palu Nomoni adalah salah
satu event bertaraf internasional yang telah
diselenggarakan dalam dua tahun terakhir.
Antusias masyarakat Palu dari kegiatan
sebelumnya, yaitu Festival Teluk Palu yang
melatarbelakanginya. Festival Teluk Palu
sendiri rutin digelar sejak 2008 dalam rangka
menyambut ulang tahun Kota Palu. Festival
tersebut berganti nama dengan menambahkan
bahasa lokal yakni “nomoni” diambil dari
bahasa etnis kaili yang berarti bergema atau
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 36
berbunyi. Salah satu tujuan praktis Festival
Pesona Palu Nomoni ini adalah untuk
meningkatkan citra Kota Palu.
Festival Pesona Palu Nomoni merupakan
terbitan pemerintah Kota Palu. Ditemui secara
khusus, Pak Gunawan selaku Kabid Destinasi
Dinas Pariwisata Kota Palu menjelaskan
bahwa dalam riwayatnya, Festival Pesona
Palu Nomoni adalah event yang
diselenggarakan pada bulan September di
pesisir teluk Kota Palu dengan durasi kurang
lebih 5 hari. “Dengan memperkenalkan serta
melestarikan adat dan budaya, melalui event
ini pemerintah berupaya menanamkan citra
terbaik untuk wisatawan nusantara maupun
mancanegara” tutur Walikota Palu, Hidayat
(www.palunomoni.com).
Namun sekali lagi tujuan sering tak sesuai
realita. Sebab dari dua edisi terakhir masih
banyak kekurangan yang juga merusak citra
Kota Palu sebagai penyelenggara sekaligus
tuan rumah. Pada Festival Pesona Palu
Nomoni edisi pertama misalnya; pembukaan
acara yang lamban, peniup lalove (seruling)
dan penabuh gimbah (gendang) yang tak jadi
tampil, hingga penyerahan hadiah jawara lari
marathon yang tertunda.
Festival Pesona Palu Nomoni edisi dua
pun tak luput dari masalah, penyerahan
hadiah untuk vocal grup juga tertunda.
Terdapat pula masalah klasik seperti biaya
pengamanan kendaraan (parkir) yang
melonjak.
Adapun temuan peneliti terkait hal yang
ditakutkan dapat merusak citra Kota Palu
sebagai berikut: Berita online yang diangkat
MetroSulawesi.com pada 26 September 2016,
dengan judul “Memaluklan, Pemenang
Lomba Marathon FPPN Tidak Langsung
Terima Hadiah”, MetroSulawesi.com pada 1
November 2016, judul berita “Setengah Total
Hadiah Palu Nomoni International Marathon
Bakal Diterima Pelari Lokal”,
SultengRaya.com pada 4 November 2016,
dengan judul “Hadiah Pemenang Marathon
Dibatalkan” & “Cita Palu Nomoni Tercemar”.
Pada 2 November 2017
RadarSultengOnline.com juga mengangkat
berita dengan judul “Sudah Sebulan, Hadiah
Palu Nomoni Belum Cair”.
Menanggapi hal tersebut, Bapak Hidayat
selaku Walikota Palu, ketika dimintai
keterangan sejumlah pers: “Ke depan panitia
bisa lebih siap dan lebih matang dalam
mempersiapkan seluruh rangkaian acara
sehingga FPPN menjadi agenda tahunan yang
bisa dibanggakan, dan semoga saja FPPN
menjadi agenda nasional, ini yang harus kita
gemakan” tutur Walikota Palu, Hidayat
(www.sultengraya.com).
Humas merupakan bagian dari struktur
kerja dalam organisasi yang memiliki tugas
membangun hubungan komunikasi yang baik
antara organisasi tersebut dengan berbagai
pihak di luar organisasi. Kegiatan humas di
pemerintah daerah Kota Palu meskipun tidak
dielu-elukan namun dalam realitanya sangat
penting peranannya, terutama dalam
membangun hubungan dan membentuk citra
positif bagi Kota Palu. Sebagai pemberi
informasi kepada publik, humas pemerintah
Kota Palu tersebut mempunyai tugas penting
yaitu memberikan informasi kepada
masyarakat luas terkait program-program
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 37
maupun kralifikasi terhadap krisis. Untuk
melakukan hal tersebut bukanlah hal mudah,
karena setiap informasi harus secara rutin
diinformasikan dan secara merata dapat
disebar luaskan kepada seluruh masyarakat
yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Event merupakan salah satu instrumen
komunikasi yang banyak dimanfaatkan oleh
perusahaan untuk memperkenalkan diri
kepada khalayaknya. Penyelenggaraan event
oleh instansi atau perusahaan biasanya
dilakukan dalam bentuk sponsorship. Oleh
karena itu, pelaksanaan event sebaiknya
dilakukan dengan perencanaan matang agar
tujuan perusahaan dalam menyelenggarakan
event tersebut dapat tercapai. Sedangkan
festival adalah hari atau pekan gembira dalam
rangka peringatan peristiwa penting dan
bersejarah misalnya pesta rakyat.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Peran Komunikasi Dalam Membangun
Citra
Komunikasi merupakan kegiatan yang
dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari
manusia. Komunikasi memainkan peran
penting bagi manusia untuk dapat
berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.
Kata komunikasi atau communication dalam
bahasa inggris berasal dari bahasa latin
communis yang berarti “sama”, communico,
communication atau comunicare yang berarti
“membuat sama” (to make common). Istilah
pertama (comunis) adalah istilah yang paling
sering sebagai asal usul komunikasi, yang
merupakan akar dari kata-kata latin lainnya
(Mulyana, 2005:4).
Menurut Abdurachman (1995: 30)
“komunikasi merupakan pesan yang
disampaikan oleh komunikator agar dapat
dimengerti komunikan, sehingga komunikator
akan mengetahui bagaimana reaksi dan
respon dari komunikan terhadap pesan yang
disampaikan”. Lebih lanjut Rachmadi (1992:
62) menyatakan bahwa, “komunikasi
merupakan proses di mana penyampaian atau
pengiriman pesan dari sumber kepada satu
atau lebih penerima dengan maksud untuk
mengubah perilaku dan sikap penerima
pesan.”
Sependapat dengan pengertian di atas,
Onong Uchjana Effendy secara paradigmatis
berpendapat bahwa, komunikasi adalah
proses penyampaian suatu pesan oleh
seseorang kepada orang lain untuk memberi
tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau
perilaku, baik langsung secara lisan maupun
tak langsung; lewat media (Effendy, 2006: 5).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pengertian citra adalah (1) kata benda:
gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang
dimiliki orang banyak mengenai pribadi,
perusahaan, organisasi atau produk; (3) kesan
mental atau bayangan visual yang
ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau
kalimat dan merupakan unsur dasar yang
khas dalam karya prosa atau puisi; (4) data
atau informasi di lapangan untuk bahan
evaluasi.
Berdasarkan pengertian di atas,
kepiawaian berbahasa menjadi salah satu
modal utama dalam berkomunikasi. Jadi, pada
dasarnya komunikasi berperan dalam
membangun citra.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 38
2. Pengertian Humas
Humas adalah suatu rangkaian kegiatan
yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai
suatu rangkaian program terpadu dan semua
itu berlangsung berkesinambungan dan
teratur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka
menciptakan dan memelihara niat baik (good-
will) dan saling pengertian antara suatu
organisasi dengan segenap khalayaknya.
Humas disebut juga public relations
(Anggoro, 2005: 9).
Secara etimologis humas atau public
relations terdiri dari dua kata; public dan
relations. Public berarti publik atau
masyarakat; dan relations adalah hubungan-
hubungan. Maka, public relations adalah
hubungan-hubungan dengan publik atau
masyarakat (Suhandang, 2004: 9).
Humas atau public relations adalah fungsi
manajemen yang khas dan mendukung
pembinaan bersama antara organisasi dengan
publiknya- menyangkut aktivitas komunikasi,
pengertian, penerimaan dan kerjasama;
melibatkan manajemen dalam menghadapi
persoalan atau permasalahan, membantu
manajemen untuk mampu menanggapi opini
publik; mendukung manajemen dalam
mengikuti dan memanfaatkan perubahan
secara efektif; bertindak sebagai sistem
peringatan dini dalam mengantisipasi miss
communication dengan teknis komunikasi
yang sehat dan etis sebagai sarana utama
(Ruslan, 2008: 16).
Adapun pendapat lain bahwa hubungan
masyarakat adalah fungsi manajemen yang
membangun dan mempertahankan hubungan
baik yang bermanfaat antara perusahaan
dengan publik dan mempengaruhi kesuksesan
atau kegagalan (Broom, 2005: 6).
Istilah Public Relation sebenarnya baru
dikenal pada abad ke 20, namun gejalanya
sudah tampak sejak abad-abad sebelumnya,
bahkan sejak manusia masih primitif. Unsur-
unsur dasarnya memberikan informasi,
membujuk dan mengintegrasikan khalayak
selalu tampak dalam kehidupan masyarakat
sejak zaman dahulu. Di zaman purbakala
orang berhubungan dengan orang lain yang
berjauhan tempatnya melalui tanda-tanda
berupa asap api di atas gunung atau tabuh-
tabuhan, tiada lain untuk menarik perhatian
dari orang lain atas dasar memelihara
hubungan baik dengan sesama. Prinsip public
relation telah pula dilakukan oleh orang-orang
Yunani dan Romawi dengan dasar-dasar vox
populi (suara rakyat) dan republika
(kepentingan umum) (Suhandang, 2004: 16).
Istilah public relation pertama kali
diperkenalkan oleh Ivy Ledbetterly pada
tahun 1906. Gagasan Lee yang ditampilkan
saat itu adalah apa yang dinamakan olehnya
declarations of participles yang membuat asas
khalayak tidak dapat diabaikan oleh
manajemen industri dan dianggap bodoh oleh
pers (Effendy, 2003: 106). Menurut Jeffkins
yang dikutip oleh Rachmadi (1994: 18), dalam
bukunya Public relation dalam teori dan
praktek menyatakan bahwa humas adalah
sesuatu yang menerangkan keseluruhan
komunikasi yang terencana, baik itu yang
keluar maupun yang ke dalam, antara suatu
organisasi dan semua khalyaknya dalam
rangka mencapai tujuan spesifikasi yang
berdasarkan pada saling pengertian.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 39
Soemirat dan Ardianto (2004: 13),
berpendat bahwa public relation merupakan
fungsi manajemen yang membantu
menciptakan dan saling memelihara alur
komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerja
sama suatu organisasi atau perusahaan
dengan publiknya dan ikut terlibat dalam
menangani masalah-masalah atau isu-isu
manajemen. Public relation membantu
manajemen dalam penyampaian informasi
dan tanggap terhadap opini publik. Public
relation secara efektif membantu manajemen
memantau berbagai perubahan.
IPRA/ International Public Relation
Assosiation mendefinisikan public relation
adalah fungsi manajemen dari ciri-ciri yang
terencana dan berkelanjutan melalui
organisasi dan lembaga swasta atau negara
untuk memperoleh pengertian, simpati dan
dukungan dari mereka yang terkait atau
mungkin ada hubungannya dengan penelitian
opini publik di antara mereka. Untuk
mengaitkannya, sedapat mungkin
kebijaksanaan dan prosedur yang mereka
pakai untuk melakukan hal itu direncanakan
dan disebarkanlah informasi yang lebih
produktif dan pemenuhan keinginan bersama
yang lebih efisien (Ardianto, 2009: 10).
Dari definisi di atas, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa pengertian public relation
adalah manajemen yang membangun suatu
hubungan dan ikatan antara organisasi
dengan publiknya dalam jangka panjang
maupun pendek sehingga tercapai suatu
tujuan yang diinginkan bersama. Tugas public
relation tidaklah hanya sekedar
berkomunikasi dengan publiknya, tetapi juga
turut mencapai tujuan dari organisasi tersebut.
Public relation itu sendiri berperan besar
dalam mengubah perilaku publik juga
menciptakan opini publik yang positif tentang
perusahaan tersebut.
Publik relation merupakan fungi
manajemen dan dalam struktur organisasi
public relation merupakan salah satu bagian
atau divisi dari organisasi. Karena itu, tujuan
public relation sebagai bagian atau divisi dari
organisasi tentu saja tidak dapat lepas dari
tujuan organisasi sendiri (Iriantara, 2005: 56-
57).
3. Peranan Humas
Pada posisi pemerintah, humas harus
memahami apa yang telah, sedang, dan akan
dilakukan oleh pemerintah termasuk di
dalamnya kebijakan program, tingkat capaian
serta persoalan yang dihadapi. Sedangkan di
posisi masyarakat humas harus mampu
memahami karakteristik dan dinamika
masyarakat (Ruslan, 2008: 21).
Peranan umum humas atau public
relations di dalam manajemen suatu
organisasi atau perusahaan yaitu
mengevaluasi sikap dan opini publik,
mengidentifikasi kebijakan dan prosedur
organisasi perusahaan dengan kepentingan
publiknya, merencanakan dan melaksanakan
kegiatan aktivitas public relations (Ruslan,
2008: 22).
Menurut Lattimore (2010) ada empat
model humas yang selalu diterapkan, yaitu:
1. Model press agentry (agen
pemberitaan) yaitu menggambarkan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 40
bagaimana informasi bergerak satu arah
dari organisasi menuju publik.
2. Model informasi publik; yaitu model
yang menggambarkan bagaimana humas
bertugas memberitahu publik. Model ini
selalu dipraktekan oleh humas
pemerintah, lembaga pendidikan dan
organisasi nirlaba.
3. Model asimetris dua arah; yaitu
memandang humas sebagai kerja persuasi
ilmiah yang menggunakan hasil riset
untuk mengukur dan menilai publik.
4. Model simetris dua arah; yaitu sebuah
model yang menggambarkan sebuah
orientasi humas di mana organisasi dan
publik saling menyesuaikan diri.
Peranan humas pemerintah adalah untuk
memberikan sanggahan mengenai
pemberitaan yang salah dan merugikan
pemerintah, dan mengkomunikasikan atau
menginformasikan berbagai kebijakan
pemerintah kepada masyarakat. Hal ini
bertujuan untuk membentuk citra positif
pemerintah daerah tersebut di mata
publiknya. Pentingnya peran humas instansi
dan lembaga perintah dalam masyarakat
modern yaitu dalam melakukan kegiatan-
kegiatan dan operasinya di berbagai tempat,
berbagai bidang. Teknik yang digunakan
dalam humas pemerintahan tidak ada
bedanya dengan teknik yang digunakan
humas di bidang lain, yaitu penyampaian
informasi dan komunikasi (Moore, 2004: 25).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
peranan humas pemerintah yaitu memberikan
informasi dan penjelasan kepada khalayak
atau publik mengenai kebijakan dan langkah-
langkah maupun tindakan yang diambil oleh
pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya
hubungan yang harmonis antara lembaga
organisasi dengan publiknya dan memberikan
pengertian kepada publik tentang apa yang
dikerjakan oleh pemerintah di mana humas
itu berada atau berperan. Menurut Dozier dan
Broom (Kusumastuti, 2002: 24) bahwa peranan
humas dibagi menjadi empat katagori yaitu:
1. Penasehat ahli (Expert Prescriber
Communication)
Seorang public relation atau humas
sudah dianggap ahli dan juga sangat
berpengalaman serta memiliki
kemampuan yang tinggi. Seorang
humas dapat menasehati seorang
pimpinan perusahaan atau top
manajemen, yang mana hubungan
mereka diibaratkan seperti hubungan
dokter dengan pasiennya. Sehingga
seorang humas dapat membantu
memecahkan permasalahan yang
tengah dihadapi perusahaan.
2. Fasilitator komunikasi
(Communication Fasilitator)
Peranan petugas humas sebagai
fasilitator komunikasi antara
perusahaan atau organisasi dengan
publik baik itu dengan publik internal
maupun dengan publik eksternal.
Istilah yang paling umum adalah
sebagai jembatan komunikasi antar
publik dengan perusahaan atau
organisasinya.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 41
3. Fasilitator proses pemecahan masalah
(Problem Solving Process Fasilitator)
Seorang humas bertindak sebagai
fasilitator dalam proses pemecahan
masalah. Pada peranan ini tugas
humas melibatkan diri atau dilibatkan
dalam setiap manajemen (krisis).
Seorang humas menjadi anggota tim,
bahkan bila memungkinkan menjadi
leader dalam penanganan krisis
manajemen.
4. Teknisi komunikasi (Communication
Technical)
Petugas humas dianggap sebagai
pelaksana teknis komunikasi. Ia
menyediakan layanan di bidang
teknis, sementara kebijakan dan
keputusan teknik komunikasi yang
akan digunakan bukan merupakan
keputusan petugas humas melainkan
keputusan manajemen dan praktisi
humas yang melaksanakannya.
Seorang humas atau public relation harus
memiliki kemampuan bergaul atau membina
hubungan dan bekerjasama dengan publik
yang berbeda-beda termasuk publik dari
berbagai tingkatan agar saling mengenal antar
publik dengan organisasi, lembaga maupun
perusahaan. Hanya dengan dukungan dan
bantuan publik-publik di sekitarnya, suatu
perusahaan ataupun organisasi dapat
mencapai tujuannya. Dukungan dan bantuan
dapat diperoleh kalau dapat diciptakan
kerjasama dan saling membantu di antara
publik-publik di sekitar perusahaan atau di
luar dari perusahaan. Dengan adanya saling
percaya satu sama lain, maka terciptalah
dukungan yang baik dan harmonis.
C. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, yaitu teknik analisa yang
memberikan informasi hanya mengenai data
yang diamati dan tidak bertujuan menguji
hipotesis serta menarik kesimpulan yang
digeneralisasikan terhadap populasi. Tujuan
deskriptif hanya menyajikan dan menganalisa
data agar bermakna dan komunikatif.
Penelitian deskriptif yaitu data-data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka sehingga
laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan
data untuk memberikan gambaran penyajian
laporan tersebut. Dasar penelitian yang
digunakan dalam penelitian dalam ini adalah
analisis sumber. Penelitian ini akan dilakukan
berdasarkan metode studi komunikator yaitu
studi mengenai komunikator sebagai individu
maupun institusi (Kriyantono 2006:12).
Komunikator yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah empat orang pejabat
humas pemda Kota Palu. Keempatnya dipilih
karena dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan
peranan humas pemda Kota Palu pada event
Festival Pesona Palu Nomoni dalam menjaga
citra Kota Palu.
D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Arti kata peranan adalah tindakan yang
dilakukan oleh seseorang, organisasi atau
kelompok dalam suatu peristiwa. Dalam hal
ini, jika ditujukan pada hal yang bersifat
kolektif, peranan memiliki makna sesuatu
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 42
yang memiliki arti positif dan diharapkan
akan mempengaruhi sesuatu yang lain.
Menurut KBBI, peranan bersinonim dengan
pengaruh. Pengaruh berarti daya yang ada
atau timbul dari sesuatu yang ikut
membentuk watak, kepercayaan atau
perbuatan seseorang.
Jika kembali dikaitkan dengan sesuatu
yang bersifat kolektif di dalam masyarakat,
maka pengaruh adalah daya yang ada atau
timbul dari organisasi yang ikut membentuk
watak, kepercayaan atau perbuatan
masyarakat. Makna peranan secara implisit
menunjukan kekuatan. Kekuatan tersebut
berlaku secara internal maupun eksternal
terhadap individu atau kelompok yang
menjalankan peranan tersebut.
Pada dasarnya yang memegang peranan
dalam tatanan kenegaraan adalah pemimpin.
Dalam hal ini untuk wilayah Sulawesi Tengah,
ada Gubernur lalu kemudian Walikota dan
Bupati. Tak sampai di situ, untuk menunjang
kinerja dan stabilitas sangat dimaklumi bahwa
pemimpin memiliki perangkat bantu dalam
bentuk satuan kerja yang terkoordinir dengan
baik. Akan mudah bagi pemimpin mencapai
tujuan bersama apabila ditunjang seperangkat
alat bantu yang professional.
Adapun pandangan lain tentang peranan,
bahwa pengertian peranan adalah kehadiran
di dalam menentukan suatu proses
keberlangsungan. Peranan yang peneliti
maksudkan dalam penelitian ini, adalah
bagaimana peranan suatu kelompok kerja
terkait suatu hal, yang dirasa menyinggung
kinerja mereka. Apakah peranan dilakukan
secara maksimal atau isapan jempol belaka.
Untuk itu, peneliti mencoba merangkum hasil
penelitian sedemikian rupa agar hal tersebut
terjawab, sebagaimana adanya.
Menurut peneliti, humas – secara umum
memiliki beberapa pengertian praktis yang
wajib diketahui. Pertama, humas dibedakan
menjadi 2 hal; jika dipandang dari sudut
pemerintahan, humas adalah satuan
kelompok kerja. Kelompok kerja yang terdiri
dari beberapa orang yang mengemban tugas
satu sama lain menjadi satu keutuhan.
Sebaliknya, jika humas bergerak di sektor
tenaga professional/ perusahaan swasta,
maka sebutan yang lebih umum adalah public
relation. Public relation adalah seorang yang
diberi kekuasaan penuh untuk bertanggung
jawab atas wajah perusahaan. Di era sekarang,
tak jarang praktisi public relation memiliki
asisten untuk membantu pekerjaanya. Namun
tetap dapat dibedakan dari humas
pemerintahan yang punya dimensi berbeda.
Perbandingan humas dan public relation
jika dilihat dari persamaannya mempunyai
kesamaan yaitu sama-sama berusaha
membangun komunikasi dua arah antara
lembaga dengan masyarakat. Adapun
beberapa pengertian praktis tentang humas
menurut peneliti, sebagai berikut:
1. Strategi komunikasi publik
Sebagai wajah dari sebuah organisasi,
humas memiliki tugas penting dalam
menyampaikan informasi organisasi
kepada stakeholder yang terkait dan
kepada publik. Setiap bagian humas
akan dilengkapi dengan narahubung
yang memungkinkan untuk menerima
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 43
keluhan dan merupakan tempat di
mana publik dapat memperoleh
informasi lengkap mengenai
organisasi. Bagian humas akan selalu
berhubungan dengan media, baik
media cetak atau elektronik. Bahkan
dewasa ini, tiap humas hampir
dipastikan memiliki online channel.
2. Mengelola keadaan darurat
Ketika sebuah kondisi menghampiri
yang terkadang dapat merusak
bahkan meruntuhkan citra sebuah
organisasi, maka di sinilah peran
penting humas dibutuhkan. Kondisi
demikan tentu tidak diharapkan,
namun isu-isu negatif selalu lebih
cepat merebak baik di dalam atau di
luar organisasi. Jika dibiarkan hal ini
akan merusak citra organisasi di mata
publik. Oleh karenanya peran humas
dalam organisasi, salah satunya untuk
meredam dan mengatasi keadaan
darurat agar tidak semakin
berkembang ke arah perpecahan.
Sehingga citra positif bisa
dipertahankan.
3. Menjangkau kegiatan
Humas terkadang senantiasa
melibatkan diri dalam sebuah
kegiatan dengan membawa brand
organisasi. Hal semacam ini tentu
akan semakin memberikan pengaruh
positif pada citra organisasi.
4. Hubungan media
Humas dan media akan selalu
bersinggungan. Apalagi jika ada
perkembangan terbaru mengenai
jalannya organisasi. Sudah tentu awak
media akan terlibat. Untuk itu humas
harus bekerja sama dengan media
untuk bisa menyiarkan perkembangan
organisasi seluas-luasnya.
5. Mengetahui dan mengevaluasi opini
publik
Seringkali opini miring akan
membawa dampak buruk bagi citra
suatu organisasi. Oleh karena itu
bagian humas harus memiliki peran
penting sebagai pihak yang harus
mengetahui isu yang sedang
berkembang dan hangat menjadi
perbincangan terutama yang
berkaitan dengan organisasi yang
dikelola. Humas harus secara sigap,
cepat tanggap dalam menganalisis
dan mengevaluasi isu yang
berkembang.
Peranan humas dalam organisasi
pemerintahan sangatlah penting. Fungsi
paling dasar humas pemerintah adalah
membantu menjabarkan dan mencapai tujuan
program pemerintahan, meningkatkan sikap
responsif pemerintah serta memberi publik
informasi yang cukup baik mengenai isu, citra
kota, dan lain sebagainya. Humas daerah
harus piawai mengedukasi masyarakat untuk
meningkatkan atau setidak-tidaknya menjaga
citra lingkungan atau daerah di mana
kelompok atau satuan humas itu bertugas.
Agar terbentuk jembatan sosial yang baik,
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 44
menguntungkan antar stakeholder dan
membangun kepercayaan.
Selain itu humas juga harus berupaya
bagaimana untuk menjalin hubungan baik
dengan media. Sebab media merupakan
publik eksternal yang menjadi sasaran
komunikasi antara humas dengan publik.
Akan ada hubungan timbal balik yang
menyenangkan untuk kedua pihak jika hal itu
terlaksana dengan baik. Melalui media massa,
humas dapat menginformasikan kepada
publik kebijakan-kebijakan yang ada,
sebaliknya media massa mendapatkan bahan
pemberitaan untuk menunjang eksistensinya.
Sesuai dengan pencapaian yang harus
dimiliki humas pada instansi pemerintah atau
kedaerahan yakni bertanggung jawab menjaga
citra positif instansi dan mencitrakan daerah
atau tempat di mana instansi tersebut
bertugas, wajib bagi perangkat humas
menginformasikan semua tindakan-tindakan
dan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan.
Dalam hal ini, humas pemda Kota Palu harus
transparan terkait keikutsertaan mereka pada
event Festival Pesona Palu Nomoni.
Citra Kota Palu yang peneliti maksud
dalam penelitian ini, yakni bagaimana
pandangan masyarakat umum tentang Kota
Palu, yang mana dalam terselenggaranya
Festival Pesona Palu Nomoni masih banyak
hal-hal yang justru berdampak tidak baik
untuk pencitraan Kota Palu. Bagaimana
peranan humas dalam mengatasi isu yang
masih akan selalu hangat untuk dibahas ini –
bagaimana tidak, menurut peneliti event
sekelas Palu Nomoni bukanlah event biasa-
biasa saja.
Berikut penuturan tegas Pak Firman,
selaku kepala sub bagian informasi dan
dokumentasi humas pemda Kota Palu: “Ya,
kami ikut serta dalam kegiatan Palu Nomoni.
Pra kegiatan, saat kegiatan maupun pasca
kegiatan.” Hal tersebut menjadi jawaban
pembuka untuk peneliti bahwasanya peranan
humas pemda Kota Palu pada event Festival
Pesona Palu Nomoni akan mudah dijabarkan
sesuai kerangka pikir yang ada.
Citra mencerminkan apa yang dipikirkan,
emosi dan persepsi individu. Walaupun orang
melihat hal yang sama, tapi pandangan
mereka bisa berbeda. Persepsi inilah yang
membentuk citra dari sebuah organisasi, baik
itu satuan kelompok kecil sampai yang
terbesar. Festival Pesona Palu Nomoni telah
diselenggarakan di Kota Palu dua periode
dalam rentan waktu 2016 – april 2018.
Perhelatan tersebut dapat dikatakan sukses
sebab pihak terkait tentu telah
memaksimalkan daya dan upaya mereka.
Seiring dengan kesuksesan
penyelenggaraan Festival Pesona Palu
Nomoni yang dalam artian lain adalah
capaian positif, tentu tak lepas juga dari
capaian negatif. Menurut peneliti, pihak
panitia masih belum cepat tanggap dengan
situasi dan kondisi di lapangan. Hal-hal kecil
tentu dapat merusak citra kota. Sebab
penilaian pada dasarnya bersifat relatif.
Katakanlah pengetahuan setiap individu
berbeda-beda, penilaian terhadap sikap atau
kejadian antar kelompok penyelenggara dan
pengunjung pasti lah berbeda.
“Citra Kota Palu adalah dunia
sekeliling kita memandang kita. Saya
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 45
pikir terlepas dari hal positif yang ada,
hal negatif selalu mengikuti. Kalau
mencari kesalahan sesuatu, suatu
kesalahan pasti dengan mudah
ditemukan. Sedangkan hal yang benar
jarang bernilai karena faktor
kepentingan.” (Hasil wawancara
tanggal 10 april 2018)
Ibu Farida selaku kepala sub bagian
humas menjawab pertanyaan peneliti dengan
kalimat bias; seolah-olah dalam penyelesaian
masalah, humas Kota Palu tentu
menyesuaikan dengan konteks persoalan. Jika
pada Festival Pesona Palu Nomoni terjadi hal-
hal yang tidak diharapkan tentu itu bagian
dari ketidaksempurnaan suatu hajatan.
Seringkali suatu festival digelar untuk
mendapatkan keuntungan dari sektor
ekonomi. Berangkat dari pandangan itu,
peneliti mengajukan pertanyaan pada kasubag
humas perihal keberhasilan kegiatan Festival
Pesona Palu Nomoni menurut humas Kota
Palu.
“Menurut kami, asalkan masyarakat
senang, nyaman dan betah maka
kegiatan tersebut dapat dikatakan
berhasil. Data dari peserta umkm
yang kami kantongi, semua yang ikut
dan turut membuka lapak di kawasan
festival mendapatkan keuntungan
finansial. Semoga ke depan kegiatan
ini bisa rutin di gelar.” (Hasil
wawancara tanggal 10 april 2018)
Jawaban berbeda peneliti temukan ketika
bertanya tentang keuntungan ekonomi dari
sudut pandang kepala sub bagian protokol,
Bapak Muhammad Nizam:
“Anggapan masyarakat umum,
mungkin FPPN sukses dilihat dari
faktor ekonomi. Tapi dilihat dari
anggaran di balik semua itu,
pendapatan daerah (dari kegiatan
tersebut) terlihat kecil.” (Hasil
wawancara tanggal 13 desember 2017)
Penting mengetahui keberhasilan kegiatan
dari sektor ekonomi setidaknya agar alasan
keberlanjutan kegiatan ini bisa diukur dan
lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Sedikit temuan di atas adalah pembuka dari
temuan-temuan yang mengejutkan terkait
peranan humas pemda Kota Palu pada event
Festival Pesona Palu Nomoni dalam menjaga
citra Kota Palu.
1. Humas Berperan Sebagai Penasehat Ahli
Pada dasarnya humas merupakan bidang
atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh
setiap organisasi baik yang bersifat komersil
atau non komersil. Keberadaan seorang
praktisi humas di suatu lembaga atau instansi
sangatlah penting untuk membantu dalam
mencapai tujuan-tujuan instansi.
Seorang praktisi atau pakar humas yang
dianggap berpengalaman dan memiliki
kemampuan tinggi dapat membantu
mencarikan solusi dalam penyelesaian
masalah hubungan dengan publiknya.
Hubungan praktisi atau pakar humas dengan
manajemen organisasi seperti hubungan
antara dokter dan pasiennya. Artinya, pihak
manajemen bertindak pasif untuk menerima
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 46
atau mempercayai apa yang telah disarankan
atau diusulkan humas selaku penasehat ahli.
Dalam dua edisi, kegiatan Festival Pesona
Palu Nomoni meninggalkan masalah klasik
seperti; biaya parkir, hadiah yang telat
diberikan, dan hal lainnya – perihal ini telah
peneliti sebutkan dalam latar belakang
penelitan. Berangkat dari hal tersebut, peneliti
akan menjabarkan peranan humas apakah
mereka dianggap sebagai penasehat ahli
terkait temuan tersebut.
Dalam wawancara singkat, kepala bagian
humas Pak Nathan menjelaskan bahwa:
“Pada kegiatan ini, humas Kota Palu
belum diberi kesempatan untuk
menjalankan peran sebagai penasehat
ahli, hal ini dibuktikan ketika masalah
perparkiran hangat dibahas,
begitupun masalah Palu Nomoni
lainnya. Adapun pihak panitia
Festival Pesona Palu Nomoni selaku
leader sector punya humas Dinas
Pariwisata yang siap memback-up
dalam hal ini menyusun strategi
terkait pemberitaan yang meresahkan
itu. Adapun dalam rapat yang
diselenggarkan dalam rangka
persiapan acara, humas maupun
atasan (walikota) tidak dimintai
tanggapannya secara langsung
bilamana kelak terjadi hal yang tidak
diinginkan.” (Wawancara tanggal 10
april 2018)
Humas merupakan bidang atau fungsi
tertentu yang diperlukan oleh setiap
organisasi, perusahaan bahkan pemerintahan.
Peran sentralnya mengatur kendaraan
komunikasi ke dalam dan ke luar. Kebutuhan
dan kehadirannya tidak bisa dicegah sebab
humas merupakan salah satu elemen yang
menentukan kelangsungan suatu organisasi
secara positif. Sebagai sebuah unit yang
mempunyai tugas untuk membangun kerja
sama, saling pengertian, saling menghargai
dengan komunikasi dua arah. Humas
merupakan fungsi manajemen yang
membentuk dan mengelola hubungan saling
menguntungkan antara organisasi dan
masyarakat (publik). Keberhasilan atau
kegagalan hubungan ini tergantung pada
fungsinya sehingga wajar humas selalu
diletakan sebagai penasehat ahli.
Namun tidak demikian pada humas Kota
Palu, di mana berada pada posisi tidak
dilibatkan pada peran ini sehingga upaya
untuk menjaga citra kota Palu pasca kegiatan
Festival Pesona Palu Nomoni bisa dikatakan
kurang maksimal.
Secara garis besar, citra adalah
seperangkat keyakinan, ide dan kesan
seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap
dan tindakan seseorang terhadap suatu objek
akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang
menampilkan kondisi terbaiknya. Bagi suatu
perusahaan atau instansi, citra diartikan
sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri
instansi tersebut. Persepsi masyarakat
terhadap perusahaan atau instansi didasari
pada apa yang mereka ketahui atau mereka
kira tentang perusahaan atau instansi yang
bersangkutan. Citra perusahaan atau instansi
yang baik dimaksudkan agar perusahaan atau
instansi dapat tetap hidup dan meningkatkan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 47
kreativitasnya bahkan memberikan manfaat
lebih bagi orang lain.
Citra merupakan tujuan dan sekaligus
merupakan reputasi dan prestasi yang hendak
dicapai. Walaupun citra merupakan sesuatu
yang abstrak dan tidak dapat diukur secara
sistematis, namun wujudnya dapat dirasakan
dari hasil penelitian baik dan buruk yang
datang dari khalayak atau masyarakat luas.
Penilaian atau tanggapan tersebut dapat
berkaitan dengan timbulnya rasa hormat
(respect), kesan-kesan yang baik yang berakar
dari nilai-nilai kepercayaan. Keberhasilan
perusahaan membangun citra dipengaruhi
oleh berbagai macam faktor.
Saat berhadapan dengan situasi yang
pelik, praktisi humas yang berpengalaman
akan bertindak sebagaimana mestinya. Sesuai
prosedural dan meminimalisir kesalahan.
Maksudnya sesuai prosedural adalah
bagaimana strategi yang dipilih. Sebagaimana
pengertian strategi yakni cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian
tujuan. Strategi humas yaitu alternatif optimal
yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai
tujuan humas dalam kerangka suatu rencana
humas.
Ditanyai lebih lanjut mengenai isu yang
sudah terlanjur merebak dan mengancam citra
Kota Palu, Pak Nathan bertutur santai
“Menanggapi isu itu jangan terlalu diseriusi.
Walaupun fakta di lapangan kayaknya berkata
demikian. Sebab faktor yang
mempengaruhinya itu luas.” Dimintai
tanggapan bahwa peran humas tidak sejalan
dengan teori yaitu baiknya humas dianggap
sebagai penasehat ahli (Expert Prescriber
Communication) Pak Nathan bertutur:
“Di Kota Palu sendiri, carut-marut
perparkiran sebenarnya cukup
mempengaruhi citra. Saat ada
kegiatan daerah berskala besar, biaya
parkir sering jadi keluhan masyarakat
yang berkunjung ke lokasi. Alasan
tukang parkir juga sering mengada-
ada; kegiatan yang tidak setiap hari
lah, menjaga ataupun mengawasi dan
menata kendaraan tidak gampang,
dan lain sebagainya. Belum lagi tidak
transparannya pendapatan daerah
dari retribusi parkir. Tapi memang
terkait biaya retribusi parkir, itu
murni perbuatan oknum yang tidak
bertanggung jawab. Kami percaya
Dinas Perhubungan sudah
memperhatikan hal ini. Masyarakat
pun harus bijak menyikapi, toh
petugas perparkiran bisa diajak bicara.
Jujur saja, mau kasih uang berapa
tidak masalah. Haha.” (Hasil
wawancara 10 april 2018)
Pak Nathan memberi tanggapan
mengenai itu dengan sangat santai. Bahkan
beliau bercerita bahwa pernah tidak bayar
parkir lantaran petugas parkir sibuk menata
kendaraan pengunjung di Festival Pesona
Palu Nomoni.
Dari hasil penelitian di atas dapat
dikatakan bahwa pada bagian ini humas
pemda Kota Palu tidak dilibatkan sebagai
penasihat ahli. Seharusnya humas dilibatkan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 48
aktif untuk menyuarakan pandangannya
terkait membantu mencarikan solusi dalam
penyelesaian masalah dengan publiknya.
Termasuk masalah yang sudah diperkirakan
sebelumnya (antisipasi).
2. Humas Berperan Sebagai Fasilitator
Komunikasi
Secara struktural humas merupakan
bagian integral dalam suatu organisasi, sebab
humas sebagai pilar terdepan atau ujung
tombak lembaga atau instansi. Kegiatannya
bermuara pada tujuan memperoleh goodwill,
kepercayaan, saling pengertian dan citra yang
baik dari masyarakat.
Humas merupakan suatu bagian dalam
organisasi atau instansi yang berperan sebagai
sarana komunikasi internal maupun eksternal
dalam suatu organisasi atau instansi. Mereka
berupaya untuk memberikan informasi
tentang segala kegiatan, kebijakan, prosedur
dan sekaligus untuk membangun
mempertahankan citra positif organisasi atau
instansi tersebut.
Humas sebagai fasilitator komunikasi
berperan sebagai komunikator atau mediator
untuk membantu pihak manajemen dalam hal
untuk mendengarkan apa yang diinginkan
dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain,
ia juga dituntut mampu menjelaskan kembali
keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi
kepada pihak publiknya. Sehingga dengan
komunikasi timbal balik tersebut dapat
tercipta saling pengertian, mempercayai,
menghargai mendukung dan toleransi yang
baik dari kedua belah pihak.
Dimintai tangapan tentang hal itu, Pak
Nathan berkata:
“Humas Kota Palu sebagai fasiltator
komunikasi, sudah menjalankan
perannya dalam penanganan isu yang
merebak terkait Palu Nomoni.
Misalnya pada penyerahan hadiah
yang tidak tepat waktu. Pada tahun
2016 kami tahu ada penyerahan
hadiah utama jawara marathon yang
dipersoalkan, dan di 2017 paduan
suara. Pemenang sudah menunggu
sampai batas yang sudah diulur,
namun tetap saja hadiah belum
dicairkan. Keterlambatan hadiah
semacam ini tentu dapat merusak citra
Kota Palu selaku tuan rumah acara
internasional tersebut. Hadiah-hadiah
lomba itu setahu kami sudah selesai.
Dalam rapat internal, kami turut
membantu dengan
mengkoordinasikan kepada atasan
(walikota) mengenai hal ini. Setiap
ada pertanyaan mengenai ini, untuk
lebih jelasnya kami menganjurkan
untuk bertanya langsung pada leader
sector masing-masing (Dinas terkait).
Hal ini adalah tanggung jawab
mereka. Namun kami siap
memfasilitasi jika menemui jalan
buntu.” (Hasil wawancara 10 april
2018)
Beliau menambahkan bahwa masalah
hadiah atau reward telah rampung urusannya
sebelum kegiatan dimulai.
“Kegiatan lomba tak mungkin
dilakukan tanpa persetujuan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 49
sebelumnya. Begitu pula mengenai
jumlah hadiah, dan kapan hadiah
diberikan. Itu sudah dibicarakan
sebelumnya sebelum hari h.” (Hasil
wawancara 10 april 2018)
Hal senada diungkapkan Pak Firman,
kepala sub bagian informasi dan dokumentasi
humas Kota Palu:
“Kalau ada pertanyaan mengenai
hadiah yang telat diberikan, tanyakan
langsung ke dinas terkait. Humas
Kota Palu tidak bertanggung jawab
langsung soal itu. Tapi juga
mengambil peranan jika ditanyai
seperti ini.” (Hasil wawancara 13
desember 2017)
Ibu Farida, selaku kepala sub bagian
humas menambahkan:
“Wartawan sering bertanya demikian
ke sini. Ada baiknya tanyakan
langsung ke dinas pariwisata. Humas
di sana yang bantu jawab. Adapun
proses pemecahan masalah, biasanya
dilakukan tertutup (internal). Saat
sudah selesai baru disiarkan lewat
media (ke publik eksternal).” (Hasil
wawancara 10 april 2018)
Dari hasil penelitian di atas dapat
dikatakan bahwa pada bagian ini humas
pemda Kota Palu sudah dilibatkan sebagai
fasilitator komunikasi. Dilihat dari reaksi
mereka ketika dimintai tanggapan tentang
bagaimana mereka membantu pihak
manajemen dalam hal untuk mendengarkan
apa yang diinginkan dan diharapkan oleh
publiknya.
3. Humas Berperan Sebagai Fasilitator
Pemecahan Masalah
Humas dianggap sebagai fasilitator dalam
proses pemecahan masalah. Pada peranan ini
tugas humas melibatkan diri atau dilibatkan
dalam setiap manajemen (krisis). Seorang
humas menjadi anggota tim, bahkan bila
memungkinkan menjadi leader dalam
penanganan krisis manajemen.
Humas sebagai fasilitator proses
pemecahan masalah memiliki peranan dalam
membantu pimpinan organisasi baik sebagai
penasehat (adviser) hingga mengambil
tindakan eksekusi (keputusan) dalam
mengatasi persoalan atau krisis yang tengah
dihadapi secara rasional dan professional.
Biasanya dalam menghadapi suatu krisis yang
terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang
dikoordinir praktisi ahli public relations
dengan melibatkan berbagai departemen dan
keahlian dalam satu tim khusus untuk
membantu organisasi, dalam hal ini atasan
(walikota) atau panitia pelaksana Festival
Pesona Palu Nomoni dalam menghadapi kriris
yang terjadi.
Untuk mengetahui peran humas sebagai
fasilitator proses pemecahan masalah, Pak
Firman bantu menjawab “Humas kota palu
kurang diandalkan sebagai fasilitator proses
pemecahan masalah. Padahal jika dibutuhkan
pasti kami siap membantu.” Jadi, masalah
yang ada pasca kegiatan palu nomoni seolah
dibiarkan reda dengan sendirinya.
Terlepas dari prokontra tanggapan publik
mengenai keberhasilan kegiatan Festival
Pesona Palu Nomoni pasca kegiatan, reaksi
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 50
humas Kota Palu selaku corong pemerintah
selalu dinantikan. Melalui humasnya
pemerintah dapat menyampaikan informasi
atau menjelaskan hal-hal yang berhubungan
dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan
tertentu serta menjelaskan aktifitas dalam
melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban
pemerintahannya.
Dalam penyelesaian masalah yang
ditakutkan dapat merusak citra Kota Palu
selaku tuan rumah. Temuan peneliti adalah
humas dilibatkan secara pasif. Hal ini
dikuatkan oleh Ibu Farida, selaku kabag
humas:
“Kami selalu membuka pintu dan
bersedia untuk menfasilitasi jika
diperlukan. Namun realitanya, kami
tidak dilibatkan. Misalnya pada
masalah berita online yang beredar.
Tak ada pihak mempersoalkan itu.
Dalam klarifikasi kebenaran berita,
humas bekerja dengan teratur agar
citra tetap dapat dijaga. Citra lembaga,
citra atasan, citra Kota Palu, citra
negeri ini.” (Hasil wawancara 10 april
2018)
Dimintai tanggapan mengenai mengapa
humas tidak dilibatkan, Pak Firman
menyebutkan:
“Peran humas dalam mensukseskan
Festival Pesona Palu Nomoni kurang
melibatkan hal-hal yang berbau
strategi. Lebih pada persoalan teknis
saja.” (Hasil wawancara 10 april)
Ditanyai secara terpisah, penanggung
jawab gelaran Festival Palu Nomoni dari
Dinas Pariwisata, Pak Gunawan menuturkan
sebagai berikut:
“Pada dasarnya humas pemda Kota
Palu termasuk dalam panitian inti
bidang kehumasan dalam gelaran
palu nomoni. Panitia inti ini kan
banyak, terdiri dari dua puluh satu
bidang. Nah, di antara bidang itu,
humas setda juga termasuk. Jika dari
sana mengaku tidak dilibatkan maka
itu karena mereka yang kurang
berperan.”
Maka dari hasil penelitian di atas, pada
bagian ini humas berperan minim dalam
upayanya menjaga citra Kota Palu. Sebab
bilamana peranan strategi dilakukan dengan
maksimal tentu saja keberhasilan menjaga
citra Kota Palu sebagai goal humas
kemungkinan dapat diraih.
4. Humas Berperan Sebagai Teknisi
Komunikasi
Petugas humas dianggap sebagai
pelaksana teknis komunikasi yang
menyediakan layanan di bidang teknis.
Sedangkan kebijakan dan keputusan teknik
komunikasi yang akan digunakan merupakan
keputusan manajemen dan praktisi humas
yang melaksanakannya. Peneliti akan
menjabarkan bagaimana hal teknis yang
dilakukan petugas humas terkait Festival
Pesona Palu Nomoni. Ditanyai mengenai hal
itu, kepala sub bagian informasi dan
dokumentasi Bapak Firman menjelaskan
santai, bahwa:
“Sebenarnya peranan humas pemda
Kota Palu pada event Festival Pesona
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 51
Palu Nomoni dalam menjaga citra
Kota Palu hanya sebatas dokumentasi
saja. Inilah hal teknis nyata yang kami
lakukan. Kami mengikuti jalannya
kegiatan dari awal – sebelum kegiatan
dimulai sampai penutupan. Ketika
ada hal yang berkaitan dengan
jeleknya citra, yang kami lakukan
dengan segera adalah berkoordinasi
pada pimpinan untuk memberikan
pemberitaan tandingan yang intinya
memberi solusi. Menyelesaikan
masalah dengan memberi bukti
dokumentasi adalah cara terbaik
menurut kami.” (Hasil wawancara 13
desember 2017)
Setelah melihat wawancara di atas peneliti
merasa bahwa peranan humas Kota Palu pada
event Festival Pesona Palu Nomoni dalam
menjaga citra Kota Palu sangat minim.
Dokumentasi yang dimaksud adalah
peliputan rangkaian acara dalam bentuk
audiovisual, bekerjasama dengan media lokal
TVRI Sulteng.
Bentuk kerjasama yang peneliti
maksudkan antara humas dan TVRI ternyata
cuma mengambil gambar yang direkam pihak
TVRI. Semacam kliping digital. Hal ini peneliti
simpulkan sebagai peranan nyata humas
sebagai teknisi komunikasi.
Hingga akhirnya timbul rasa penasaran
lanjutan tentang peranan humas Kota Palu
terkait mempromosikan kegiatan Palu
Nomoni.
“Tidak ada. Humas Kota Palu juga
tidak mempromosikan apapun
sebelum kegiatan Palu Nomoni
digelar. Ucapan sukseskan kegiatan
pesona Palu Nomoni itu yang ada di
mobil-mobil Dinas, bukan kinerja
kami. Itu Dinas masing-masing punya
kepentingan untuk
mempromosikannya. Sudah ada
anggaran untuk itu di panitia inti
bidang publikasi. Kami ya hanya
dokumentasi. Itu saja.” (Hasil
wawancara 13 desember 2017)
Ibu Farida menambahkan:
“Mengawal kegiatan pimpinan sudah
menjadi tupoksi kami. Jadi kalau
pemimpin ada di mana, ya kami ke
sana, pun jika kepemerintahannya
dikritik, kami back-up.” (Hasil
wawancara 10 april 2018)
Melihat jawaban wawancara di atas,
peneliti sadar bahwa kinerja suatu humas,
tidak selalu sesuai harapan. Dokumentasi
bentuk audiovisual sudah cukup untuk
menjawab peranan humas Kota Palu dalam
menjaga citra Kota Palu.
Dalam riwayatnya, tanggung jawab teknis
komunikasi diemban oleh seluruh staff
kepegawaian di bagian humas pemerintah
daerah Kota Palu. Hal ini dikuatkan oleh
pernyataan Ibu Farida sebagai berikut:
“Seluruh pegawai di bagian humas
Kota Palu berperan aktif dalam
pelayanan teknis komunikasi.
Katakanlah ada masyarakat yang
datang ke kantor dan meminta
penjelasan, atau misalnya temuan
tentang isu, pasti segera
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 52
mengkoordinasikan bersama
pimpinan yang ada.” (Hasil
wawancara 10 april 2018)
Penjelasan kasubag humas
menggambarkan aksi cepat tanggap yang
sudah dilakukan dengan baik. Selain itu
menjelaskan bahwa teori Dozier dan Broom
tentang Teknisi Komunikasi (Communication
Technical) adalah elemen tak terpisahkan dari
tiga peranan humas sebelumnya. Pak Nizam,
selaku kasubag protokol humas
menambahkan:
“Pada waktu peliputan dokumentasi
kegiatan FPPN, kami, seluruh
pegawai dan staff turut menghadiri
kegiatan sambil melakukan
dokumentasi. Dokumentasinya dalam
bentuk foto dan video recorder. Sudah
ada tim yang dibentuk untuk kegiatan
itu. Adapun jika diperlukan, pasca
kegiatan kami bisa saja membuat
press release. Kami menyediakan
ruang konfrensi pers untuk rekan-
rekan media bisa bertanya apa saja.”
Dilihat dari wawancara di atas, peneliti
menemukan penjelasan bahwa seluruh staff di
bagian humas Kota Palu yang berjumlah 25
orang terlibat dalam proses dokumentasi
kegiatan Festival Pesona Palu Nomoni.
Secara keseluruhan, peneliti menemukan
fakta bahwa humas Kota Palu juga memiliki
media partner yang mana hubungan mereka
dengan media tersebut selalu mencoba untuk
membangun hubungan baik dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas.
Disediakan pula fasilitas-fasilitas pendukung
yang dapat membantu awak media untuk
melaksanakan tugasnya.
Humas Kota Palu juga senantiasa
menyediakan atau memasok materi-materi
yang akurat terkait kegiatan-kegiatan yang
dilakukan humas pemda Kota Palu. Sehingga
dengan sikap seperti ini, humas dinilai punya
sumber informasi yang akurat dan dapat
dipercaya sebagai corong pemerintahan
Hidayat-Pasha, sehingga dengan begitu secara
otomatis juga akan berdampak baik terhadap
reputasi instansi dan citra kota pada
umumnya.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan dari seluruh hasil
pembahasan yang terdapat pada uraian di
atas, maka pada bab ini penulis dapat menarik
kesimpulan dari permasalahan yang diajukan
sebelumnya yaitu bagaimana peranan humas
pemda Kota Palu pada event Festival Pesona
Palu Nomoni dalam menjaga citra Kota Palu.
Setelah melihat hasil penelitian yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada
bagian ini peneliti menarik kesimpulan
bahwa: Peranan humas pemda Kota Palu pada
event Festival Pesona Palu Nomoni dalam
menjaga Citra Kota Palu sudah dimulai sejak
tahap perencanaan kegiatan. Humas pemda
Kota Palu hanya terlibat aktif dalam
dokumentasi/ liputan acara selama hari h
hingga penutupan. Dokumentasi yang
dimaksud adalah peliputan rangkaian acara.
Segala bentuk promosi atau publikasi yang
ada di dalam kegiatan Festival Pesona Palu
Nomoni tidak melibatkan humas pemda Kota
Palu. Sebab di dinas pariwisata sudah ada
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 53
kasubag promosi yang memprogramkan itu.
Menurut humas pemda Kota Palu, event
Festival Pesona Palu Nomoni berjalan sukses.
Terlepas dari ada pemberitaan yang tidak
menyenangkan. Humas pemda Kota Palu
turut andil dalam mensuksekan kegiatan
Festival Pesona Palu Nomoni dengan ikut
serta dalam rangkaian acara, dalam hal ini
meliput kegiatan dan meminimalisir isu yang
berkaitan dengan citra Kota Palu. Humas
pemda Kota Palu menyediakan ruang khusus
untuk kegiatan peliputan yang disebut dengan
ruang konfrensi pers. Dalam ruang konfrensi
pers tersebut, terdapat fasilitas-fasilitas yang
sesuai dengan kebutuhan dasar para awak
media, yaitu perangkat komputer, jaringan
internet, makanan ringan atau snack dan air
minum yang disediakan oleh pihak humas
pemda Kota Palu. Pihak humas pemda Kota
Palu senantiasa menyediakan atau memasok
materi-materi yang akurat terkait kegiatan-
kegiatan kinerja humas pemda , sehingga
dengan sikap seperti ini humas dinilai sebagai
suatu sumber informasi yang akurat dan
dapat dipercayai oleh pihak media. Peran
strategis yang tidak maksimal hanya akan
membuat peran teknis tidak begitu bernilai.
Harusnya humas pemda Kota Palu dapat
memaksimalkan seluruh sumber daya yang
ada agar teori bisa sejalan dengan praktek.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman. 1995. Dasar-Dasar Public
Relation. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti
Anggoro, Linggar. 2005. Teori dan Profesi
Kehumasan Serta Aplikasinya di
Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Ardianto, Elvinaro 2009. Publik Relation
Paktis. Edisi Pertama. Bandung:
Simbiosa Rekatama Media
Ardianto, Elvinaro. 2007. Komunikasi Massa
Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa
Rekatama Media
Ardianto, Elvinaro. 2011. Handbook of Public
Relation. Bandung: Simbiosa Rekatama
Media
Arikunto. 2001. Prosedur Penelitian. Jakarta:
Bina Aksara
Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian.
Jakarta: Rineka Cipta
Aziz, Alimul. 2003. Riset Keperawatan &
Teknik Penulisan Ilmiah. Jakarta:
Salemba Medika
Broom, Glen. 2005. Effective Public Relation.
Edisi Kesembilan. Terjemahan. Jakarta:
Kencana
Bugin. 2009. Analisis Penelitian Data
Kualatatif. Jakarta: Raja Grafindo
Danandjaya. 2011. Peranan Humas Dalam
Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
Effendy, Onong Uchjana. 2002. Suatu Studi
Hubungan Masyarakat. Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya
Effendy, Onong Uchjana. 2006. Ilmu
Komunikasi Teori dan Praktek.
Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
https://web.facebook.com/groups/InfoKotaP
ALU/
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 54
Iriantara, Yosel. 2004. Manajemen Strategis
Publik Relation. Jakarta: Ghalia
Indonesia
Iriantara, Yosel. 2005. Media Relation Konsep,
Pendekatan dan Praktik. Cetakan
Pertama. Bandung: Simbiosa Rekatama
Media
Kriyantono. 2006. Teknis Praktis Riset
Komunikasi. Jakarta: PT. Kencana
Perdana
Kusumastuti. 2002. Dasar-Dasar Humas, Edisi
Pertama. Jakarta Selatan: PT. Ghalia
Indonesia
Lattimore. 2010. Public Relation Profesi dan
Praktek. Jakarta: Salemba Medika
Lubis, Evawani Elysa. 2012. Jurnal Penelitian:
Peran Humas Dalam Membentuk Citra
Pemerintah. FISIP Universitas Riau
Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosda Karya
Moleong. 2008. Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja Rosda Karya
Moore, Frazier. 2004. Humas Membangun
Citra dan Komunikasi. Bandung:
Remaja Rosda Karya
Mulyana, Deddy. 2004. Metodelogi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya
Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi
Suatu Pengantar. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Mulyana, Deddy. 2006. Ilmu Komunikasi
Sebagai Pengantar. Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya
Rachmadi. 1992. Public Relation dalam Teori
dan Praktek. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Rachmadi. 1994. Public Relation dalam Teori
dan Praktek. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen BMT.
Yogyakarta: UII Press
Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Publik
Relation dan Media. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada
Soemirat & Ardianto. 2007. Dasar-dasar Public
Relation. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta
Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar
Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk
dan Kode Etik. Bandung: Nuansa.
Sukatendel, Arko. 1990. Public Relation
Perusahaan. Bandung; FIKOM UNPAD
Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta:
Salemba Empat
Walgito, Bimo. 2010. Psikologi Pendidikan.
Yogyakarta: Ar-Ruz Media
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 55
Widjaja, Amin. 2008. Dasar-Dasar Customer
Relation Menagement. Jakarta:
Harvindo
www.metrosulteng.com
www.palunomoni.com
www.radarsultengonline.com
www.sultengraya.com
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 56
COMMUNICATION CLIMATE ON PALU TRASHBAG COMMUNITIES
IKLIM KOMUNIKASI PADA KOMUNITAS TRASHBAG PALU
DWI DESRIANITA1
1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah E-mail: [email protected]
Naskah diterima : 7 Juni 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
This research is a qualitative descriptive study. The purpose of this study was to find out how the
communication climate took place in the Trashbag community activities. To see how the communication
climate in the Trashbag community researchers see using five dimensions of communication climate according
to Redding and Goldhaber. Namely Supportiveness or mutual support, participation, trust, openness, and high
performance goals. From these five points the researchers also analyzed how the communication process was
of two types, namely horizontal communication and vertical communication. In this study, researchers
approached participant observation which required researchers to take part in the Sapu Jagad 2017 activity,
which is a routine activity held by Trashbag every year. The results of this thesis are Trashbag members who
always provide support in terms of decision making and when members will carry out their respective duties.
Palu Trashbag members and Jagad Sweep committee also participate voluntarily. Members / volunteers
Trashbag put so far have had a sense of trust in each other member but not yet comprehensive. Trashbag is a
community that implements a non-binding flexible system so that members can be more open. When all
members feel open to each other to achieve the community's vision and mission according to researchers, it can
be more maximal.
Keywords : climate, communication, Trashbag Community
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu
bagaimana iklim komunikasi yang berlangsung dalam aktivitas komunitas Trashbag. Untuk melihat
bagaimana iklim komunikasi dalam komunitas Trashbag peneliti melihat dengan menggunakan lima dimensi
dari iklim komunikasi menurut Redding dan Goldhaber. Yaitu Supportiveness atau saling mendukung,
partisipasi, kepercayaan, keterbukaan, dan tujuan kinerja yang tinggi. Dari lima poin tersebut peneliti juga
menganalisa bagaimana proses komunikasi dengan dua jenis yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi
vertikal. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan dengan cara observasi partisipan yang
mengharuskan peneliti ikut dalam kegiatan Sapu Jagad 2017 yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan
rutin yang diadakan Trashbag setiap tahunnya. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah anggota Trashbag
selalu memberi dukungan dalam hal pengambilan keputusan dan ketika anggota akan melakukan tugasnya
masing-masing. Anggota Trashbag Palu dan panitia Sapu Jagad juga berpartisipasi secara sukarela.
Anggota/sukarelawan Trashbag menaruh sejauh ini sudah memiliki rasa percaya akan masing-masing
anggota lain tetapi belum menyeluruh. Trashbag adalah komunitas yang memberlakukan sistem fleksibel
tidak mengikat sehingga membuat para anggota bisa lebih terbuka. Ketika semua anggota merasa terbuka satu
sama lain untuk mencapai visi dan misi komunitas menurut peneliti bisa lebih maksimal.
Kata Kunci : iklim, komunikasi, komunitas Trashbag
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 57
A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, keadaan lingkungan hidup
semakin tidak terawat. Terlihat dari
banyaknya permasalahan-permasalahan
tentang lingkungan. Mulai dari kurang
sadarnya manusia tentang bahaya sampah,
penggundulan hutan yang menyebabkan
banjir dan bencana alam lainnya. Semua itu
disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak
merawat lingkungan tempat hidup mereka.
Sehingga semakin lama semakin banyak
masalah yang ditimbulkan karena lingkungan
yang kurang terawat.
Melihat masalah ini terbentuklah satu
komunitas peduli lingkungan yaitu Trashbag.
Arti dari Trashbag adalah kantung yang
digunakan untuk membuang sampah.
Disinilah trashbag (kantung sampah)
berfungsi untuk mengangkut sampah-
sampah, dari trashbag itulah beberapa
volunteer yang memiliki jiwa sosial dan
peduli terhadap kelestarian lingkungan
terutama hutan dan gunung terinspirasi untuk
membentuk sebuah perkumpulan dengan
nama Trashbag Community. Trashbag
Community itu sendiri merupakan sebuah
gerakan moral, kampanye idealis berbentuk
komunitas (nonprofit) yang anggotanya
berasal dari berbagai organisasi, kalangan
bebas ataupun independent di seluruh
Indonesia. Trashbag Community adalah
sekelompok pendaki multi disiplin ilmu yang
berdedikasi menjaga kelestarian dan keasrian
alam dengan cara mengurangi masalah
sampah digunung serta menjunjung tinggi
penerapan konservasi alam.
Trashbag Palu memiliki sejumlah kegiatan
yang sudah pernah dilakukan untuk
memerangi sampah yang ada di objek wisata
khususnya di gunung dan hutan. Pada
awalnya Trashbag dibentuk di Jakarta tetapi
sekarang sudah banyak Komunitas Trashbag
dibentuk di kota-kota besar Indonesia salah
satunya di Kota Palu. Hal ini dilakukan karena
berdasarkan dari Visi Trashbag community
yaitu ”Menjadikan Hutan Gunung di
Indonesia terbebas dari sampah”.
Trashbag memiliki banyak anggota
didalamnya, dengan berbagai macam latar
belakang. Mulai dari individu ataupun yang
tergabung dalam Komunitas Pencinta Alam
(KPA) dan Mahasiswa Pencinta Alam
(MAPALA). Beragamnya latar belakang
anggota Trashbag Palu dikarenakan proses
pengrekrutan anggota yang dibuka secara
sukarela, tidak melalui ritual-ritual khusus
yang dilakukan organisasi lain pada
umumnya. Seperti penerimaan anggota baru
yang mengharuskan mereka mengikuti
beberapa kegiatan wajib yaitu pendidikan
latihan dasar, pengabdian pada lembaga,
setelah itu lalu mereka akan naik jenjang. Hal
ini menyebabkan komunikasi yang kurang
lancar. Dikarenakan anggota Trashbag Palu
yang mempunyai organisasi masing-masing
mereka cenderung berkomunikasi sesama
anggota organisasi itu sendiri. Dan hal itu juga
terjadi kepada anggota-anggota lainnya.
Ketika anggota Trashbag itu tidak mempunyai
latar belakang organisasi, mereka akan
menjauh dengan sendirinya. Mereka hanya
akan aktif kembali ketika ada kegiatan yang di
buat oleh Trashbag Palu. Begitu pula dengan
proses komunikasinya, mereka hanya akan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 58
aktif berkomunikasi ketika ada kegiatan yang
akan dilaksanakan Trashbag Palu. Mulai dari
persiapan kegiatan, pembentukan panitia,
selama kegiatan dan pasca kegiatan.
Dalam kelompok, organisasi, dan
masyarakat, komunikasi adalah sarana yang
dapat mempertemukan kebutuhan dan tujuan
kita sendiri dengan kebutuhan dan tujuan
pihak lain (Hamad, 2013:17). Beragamnya latar
belakang yang dimiliki anggota-anggota
Trashbag Palumemicu perbedaan, mulai dari
perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran
sampai perbedaan aksi. Tidak sedikit pula
komunitas peduli lingkungan yang akhirnya
“ngambang” tidak ada kejelasan apa
sebenarnya tujuan yang ingin dicapai. Melalui
komunikasilah kita membangun hubungan
dengan berbagai macam jenis hubungan,
seperti didalam organisasi terdapat masalah,
penyelesaian pasti dengan berkomunikasi.
Yang menjadi penyebab lain kurang baiknya
komunikasi antar anggota Trashbag adalah
selain latar belakang organisasi yang berbeda-
beda, jarak tempat tinggal para anggota juga
yang berjauhan. Camp komunitas Trashbag
yang bertempat di Jalan Otista menyebabkan
para anggota kesulitan untuk selalu datang
dan berkumpul bersama anggota lainnya.
Terlebih lagi ketua Trashbag sedang berada di
luar kota untuk menyelesaikan studinya.
Kurang koordinasi antar anggota Trashbag
juga menyebabkan kurangnya item kegiatan
yang dilakukan dalam beberapa waktu.
Dalam hal ini koordinasi yang dimaksud
adalah pengurus yang kurang
memberitahukan terkait perkembangan
Trashbag. Karena untuk mengumpulkan
anggota bukanlah hal yang mudah. Karena
banyaknya perbedaan latar belakang dan
kurang komunikasi semakin lama para
anggota sudah mulai sibuk dengan kegiatan
pribadi mereka masing-masing.
Melihat hal ini, peneliti tertarik untuk
melihat bagaimana iklim komunikasi dalam
Komunitas Trashbag Palu. Karena yang
membuat masing-masing anggota memiliki
rasa termarginal adalah kurang lancarnya
komunikasi. Faktor utama yang membuat
iklim komunikasi suatu kelompok menjadi
baik adalah dengan menjaga agar proses
komunikasi tidak putus. Dengan seringnya
berkomunikasi maka akan membuat masing-
masing anggota tersebut memiliki ikatan yang
kuat. Iklim komunikasi ditentukan oleh
bermacam-macam faktor di antaranya tingkah
laku pemimpin, tingkah laku teman sekerja,
dan tingkah laku dari organisasi (Muhammad,
1995:86)
Tetapi menurut praobservasi yang peneliti
lakukan, bahwa status keanggotaan Trashbag
Palu yang belum tetap. Bahkan mereka yang
menjadi perintis terbentuknya Trashbag Palu
memiliki status keanggotaan yang tetap tetapi
bersifat sementara. Mereka hanya sebagai
anggota tetap sementara sampai pada waktu
yang tidak ditentukan. Hal ini membuat
munculnya kesenjangan sosial antar anggota,
karena mereka yang sudah pernah bergabung
sebagai sukarelawan tidak mendapat
kesempatan yang sama menjadi pengurus di
Trashbag walaupun statusnya sebagai anggota
tidak tetap. Tidak meratanya pembagian
kesempatan untuk menjadi pengurus dalam
Trashbag Palu banyak membuat sebagian
orang yang pernah bergabung sebagai
sukarelawan merasa bosan. Akibatnya mereka
mulai merasa kurang tertarik untuk mengikuti
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 59
dan menjalankan apa yang menjadi visi misi
Trashbag Palu.
Selain karena belum adanya status
keanggotaan yang tetap, masalah lain juga
muncul dari segi program kerja. Trashbag
untuk sekarang ini hanya memiliki 4 orang
anggota tetap. Yaitu ketua, wakil ketua,
sekretaris, dan bendahara. Hal ini membuat
Trashbag Palu terhambat untuk membuat
program kerja karena kesulitan dengan
anggota yang akan menjalankan program
tersebut. Lamanya proses pengajuan program
kerja juga membuat anggota tetap
kebingungan bagaimana agar bisa terus
menjalankan aktivitas kelompok.
Dalam hal item program kerja, Trashbag
Palu biasanya menunggu program kerja rutin
dari pusat. Ketika Trashbag Palu sudah
memiliki program kerja, maka mereka harus
mengajukan ke Trashbag yang ada di Jakarta
terlebih dahulu untuk disetujui lalu kemudian
dirundingkan apakah layak untuk disetujui
atau tidak.Inilah mengapa peneliti tertarik
untuk mengamati masalah yang ada di
Trashbag Palu. Karena kurangnya komunikasi
antar anggota baik sesama anggota Trashbag
Palu ataupun anggota Trashbag yang ada di
Jakarta, dan lamanya proses pengajuan
program kerja membuat anggota Trashbag
Palu semakin lama semakin malas dalam
melakukan aktivitas komunitas.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Komunikasi Organisasi
Istilah “organisasi” dalam bahasa
Indonesia atau Organization dalam bahasa
Inggris bersumber pada perkataan Latin pula,
Organizare, yang berarti to form as or into a
whole consisting of interdependent or
coordinated parts (membentuk sebagai atau
menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang
saling bergantung atau terkoordinasi). Jadi,
secara harfiah organisasi itu berarti paduan
dari bagian-bagian yang satu sama lainnya
saling bergantung. (Uchjana, 2013:114). Karl
Weick dalam Littlejohn and Foss (2008:364-
365) mengatakan bahwa dalam berorganisasi
komunikasi sangat penting karena komunikasi
sebagai sebuah dasar bagi pengorganisasian
manusia dan memberikan sebuah dasar
pemikiran untuk memahami bagaimana
manusia berorganisasi. Karl Weick juga
mengatakan organisasi bukanlah susunan
yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi
oleh aktivitas komunikasi.
Evert M. Rogers dan Rekha Agarwala
Rogers dalam bukunya, Communication in
Organization,dalam Uchjana (2013:114)
menyebut paduan tadi suatu sistem. Secara
lengkap organisasi didefinisikannya sebagai
“a stable system of individuals who work
together to achieve, through a hierarchy of
ranks and division of labour, common
goals.”(suatu sistem yang mapan dari mereka
yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama, melalui suatu jenjang kepangkatan
dan pembagian tugas). Rogers memandang
organisasi suatu struktur yang
melangsungkan proses pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan dimana operasi dan
interaksi di antara bagian yang satu dengan
yang lainnya dan manusia satu dengan
lainnya berjalan secara harmonis, dinamis,
dan pasti.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 60
Menurut Robert Bonnington dan Berverd
E. Needles, Jr dalam bukunya yang ditulis
bersama berjudul Modern Business: A
Systems Approach dalam Uchjana (2013:115)
Mereka mendefinisikan organisasi sebagai
“Organization is the means management
coordinates material and human resources
through the design of a formal structure of
tasks and authority.”(Organisasi adalah sarana
di mana manajemen mengoordinasikan
sumber bahan dan sumber daya manusia
melalui pola struktur formal dari tugas-tugas
dan wewenang.) Organisasi dan manajemen
sama pentingnya sebab secara bersama-sama
berusaha mencapai tujuan yang sama.
Manajemen sebagai kegiatan mengelola
sumber daya manusia, sumber dana, dan
sumber-sumber lainnya tidak akan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien tanpa organisasi yang mapan. Untuk
membedakan komunikasi organisasi dengan
komunikasi yang ada di luar organisasi adalah
struktur hierarki yang merupakan
karakteristik dari setiap organisasi (Thoha,
2010:186).
Redding dan Sanborn mengatakan bahwa
komunikasi organisasi adalah pengiriman dan
penerimaan informasi dalam organisasi yang
kompleks. (Muhammad, 1995:65). Hubungan
organisasi dengan komunikasi, William V.
Hanney dalam bukunya, Communication and
Organizational Behavior, menyatakan,
Organization consists of a number of people; it
involves interdependence; interdependence
alls for coordination; and coordination
requires communication.” Organisasi terdiri
atas sejumlah orang; ia melibatkan keadaan
saling bergantung; kebergantungan
memerlukan koordinasi; koordinasi
mensyaratkan komunikasi.) (Uchjana,
2013:116). Organisasi merupakan satuan yang
luas, memiliki banyak pola pikir didalamnya.
Jika semua hal itu tidak disatukan dengan
komunikasi maka organisasi tersebut akan
hancur dan tidak akan bertahan. Menurut
Harold D. Lassswell dalam Cangara (2011:2-3),
ada tiga fungsi dasar mengapa manusia perlu
berkomunikasi :
Pertama, adalah hasrat manusia untuk
mengontrol lingkungannya. Melalui
komunikasi manusia yang tergabung dalam
satu wadah atau organisasi bisa
memanfaatkan peluang yang ada, bisa
mengetahui apa halangan yang ada di dalam
organisasi, dan dapat menghindari hal-hal
yang berpotensi mengancam keberlangsungan
organisasi. Kedua, adalah upaya manusia
untuk dapat beradaptasi dengan
lingkungannya. Pada poin ini, dengan
berkomunikasi manusia dapat beradaptasi
dengan lingkungan yang baru. Jika dalam
berorganisasi, berkomunikasi dapat
mempermudah proses belajar dan
menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di
dalam organisasi. Ketiga, adalah upaya untuk
melakukan transformasi warisan sosialisasi.
Suatu masyarakat yang ingin
mempertahankan keberadaannya, maka
anggota masyarakatnya dituntut untuk
melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan
peranan. Jika dilihat dalam ruang lingkup
organisasi, komunikasi dilakukan untuk
saling berbagi ilmu, pengalaman, dan
memperlihatkan siapa mereka sebenarnya.
Hal itu dapat dilihat dari bagaimana caranya
bertindak dan mengambil keputusan.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 61
Untuk mengarahkan perilaku individu ke
arah perilaku organisasi dapat dilakukan
dengan berbagai cara (Wursanto, 2005:277-
278) antara lain : (1) Memberikan pengertian
bahwa kegagalan mencapai tujuan organisasi
juga merupakan kegagalan bagi setiap
individu dalam usaha memenuhi kebutuhan
pribadinya. Sebaiknya, apabila tujuan
organisasi dapat tercapai secara efisien maka
organisasi dapat diharapkan akan dapat
memenuhi berbagai kebutuhan para
anggotanya. Dengan demikian kegagalan
dalam mencapai tujuan organisasi tidak hanya
merugikan para pemimpin, tetapi juga
merugikan para anggota organisasi, baik
secara individu maupun secara kelompok. (2)
Dengan menjalankan teknik-teknik
kepemimpinan yang cocok, misalnya dengan
teknik persuasif, teknik penerangan, teknik
propaganda dan teknik komunikasi. (3)
Menetapkan berbagai ketentuan dan
peraturan yang harus ditaati setiap anggota,
yang diikuti dengan pemberian sangsi bagi
mereka yang melanggar ketentuan tersebut.
(4) Meningkatkat hubungan dalam organisasi
khususnya hubungan personal yang serasi di
kalangan para anggota, sehingga tercipta
loyalitas yang tinggi, baik loyalitas antara
pemimpin dengan bawahan dan sebaiknya
maupun loyalitas antara sesama
anggota/bawahan. (5) Memberikan
kesempatan kepada para anggota untuk
memberikan saran-saran yang berhubungan
dengan kepentingan organisasi, jadi pimpinan
lebih bersifat terbuka.
2. Komunikasi Kelompok
Menurut Arifin (1984:30) komunikasi
kelompok adalah komunikasi yang
berlangsung antara beberapa orang dalam
suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat,
pertemuan, konfrensi dan sebagainya.
Menurut Michael Burgoon dalam Wiryanto
(2005:63), komunikasi kelompok sebagai
interaksi tatap muka antara tiga orang atau
lebih, dengan tujuan yang telah diketahui,
seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan
pemecahan masalah, dimana seluruh
anggotanya dapat mengingat karakteristik
pribadi anggota-anggota yang lain secara
tepat.
Curtis et.al, (2005:149) menyatakan
komunikasi kelompok terjadi ketika tiga orang
atau lebih bertatap muka, biasanya dibawah
pengarahan seorang pemimpin untuk
mencapai tujuan atau sasaran bersama dan
mempengaruhi satu sama lain. Ada empat
elemen yang tercakup dalam definisi di atas,
yaitu : (1) Interaksi tatap muka, jumlah
partisipan yang terlibat dalam interaksi,
maksud atau tujuan yang dikehendaki dan
kemampuan anggota untuk dapat
menumbuhkan karakteristik pribadi anggota
lainnya. (2) Terminologi tatap muka (face-to-
face) mengandung makna bahwa setiap
anggota kelompok harus dapat melihat dan
mendengar anggota lainnya dan juga harus
dapat mengatur umpan balik secara verbal
maupun nonverbal dari setiap anggotanya.
Dengan demikian, makna tatap muka tersebut
berkaitan erat dengan adanya interaksi
diantara semua anggota kelompok. (3)
Maksud atau tujuan yang dikehendaki sebagai
elemen ketiga dari definisi diatas, bermakna
bahwa maksud dan tujuan tersebut akan
memberikan beberapa tipe identitas
kelompok. Jika tujuan kelompok tersebut
adalah berbagi informasi, maka komunikasi
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 62
yang dilakukan dimaksudkan untuk
menanamkan pengetahuan (to impart
knowledge). Sementara kelompok yang
memiliki tujuan pemeliharaan diri (self-
maintenance), biasanya memusatkan
perhatiannya pada anggota kelompok atau
struktur dari kelompok itu sendiri. Tindak
komunikasi yang dihasilkan adalah kepuasan
kebutuhan pribadi, kepuasan kebutuhan
kolektif/kelompok bahkan kelangsungan
hidup dari kelompok itu sendiri. Dan jika
tujuan kelompok adalah upaya pemecahan
masalah, maka kelompok tersebut biasanya
melibatkan beberapa tipe pembuatan
keputusan untuk mengurangi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi. (4) Kemampuan
anggota kelompok untuk menunjukkan
karakteristik personal anggota lainnya secara
akurat. Dalam hal ini, mengandung arti bahwa
setiap anggota kelompok secara tidak
langsung berhubungan dengan satu sama lain
dan maksud/tujuan kelompok telah
terdefinisikan dengan jelas, di samping itu
identifikasi setiap anggota dengan
kelompoknya relatif stabil dan permanen.
Fungsi komunikasi kelompok terbagi
menjadi 4, yaitu : (1) Menjalin hubungan sosial
antar anggota dan kelompok. Bagaimana
individu dalam suatu kelompok bisa
berhubungan sosial tanpa komunikasi atau
sejauh mana suatu kelompok dapat
memelihara hubungan sosial diantara anggota
dengan anggota atau pun anggota dengan
kelompok. (2) Fungsi pendidikan atau
edukasi. Hal ini berkaitan dengan pertukaran
informasi antar anggota akan informasi baru
dapat terpenuhi. Dan secara tidak langsung
kemampuan para anggota dibidangnya
masing-masing dapat membawa pengetahuan
baru atau justru membawa keuntungan untuk
para anggota lainnya ataupun bagi kelompok.
Latar belakang pendidikan yang berbeda
memungkinkan pemasukan jalan alternatif
dari banyak sudut pandang, sehingga akan
lebih bijaksana dalam pengambilan suatu
keputusan. (3) Kemampuan persuasi. Yaitu
bagaimana anggota kelompok berusaha mem-
persuasi anggota kelompok lainnya untuk
tidak atau melakukan sesuatu. Jika ia mem-
persuasi suatu yang sejalan dengan kelompok,
maka ia akan diterima dan menciptakan iklim
yang positif di dalam kelompok, tapi
sebaliknya jika ia mem-persuasi suatu yang
bertentangan dengan kelompok, maka akan
berpotensi menciptakan konflik dan
perpecahan di dalam kelompok. (4) Sebagai
terapi. Fungsi lebih berfokus pada membantu
diri sendiri, bukan membantu kelompok.
Disini para individu yang memiliki masalah
yang sama dikumpulkan, dan mereka diminta
untuk saling terbuka dalam mengungkapkan
diri mereka ataupun masalah mereka. Dalam
kelompok ini juga tetap membutuhkan
pemimpin sebagai pengatur dan penengah
jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat.
(http://kuliah.dagdigdug.com)
3. Klasifikasi Kelompok dan Karakteristik
Komunikasinya
Di dalam klasifikasi kelompok
komunikasi, para ahli psikologi telah
mengembangkan berbagai cara, ada tiga cara
untuk mengklasifikasikan kelompok
(Rakhmat, 1994:42). (1) Kelompok Primer dan
Sekunder, Cooley dalam Rakhmat (1994:42)
mengatakan bahwa kelompok primer adalah
suatu kelompok yang anggota-anggotanya
berhubungan akrab, personal, dan menyentuh
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 63
hati dalam sosialisasi dan kerja sama;
sedangkan kelompok sekunder adalah
kelompok yang anggota-anggotanya
berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan
tidak menyentuh hati. (2) Kelompok
Keanggotaan dan Kelompok Rujukan,
Menurut Newcomb dalam Rakhmat (1994:43),
kelompok keanggotaan adalah kelompok yang
anggota-anggotanya secara administratif dan
fisik menjadi anggota kelompok itu;
sedangkan kelompok rujukan adalah
kelompok yang digunakan sebagai alat ukur
(standar) untuk menilai diri sendiri atau untuk
membentuk sikap. (3) Kelompok Deskriptif
dan Kelompok Preskriptif, Cragan et.al, dalam
Rakhmat (1994:44) membagi kelompok
menjadi dua, yaitu kelompok deskriptif dan
preskriptif. Kelompok deskriptif menunjukkan
klasifikasi kelompok dengan melihat proses
pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan
tujuan, ukuran, dan pola komunikasi,
kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga,
yakni kelompok tugas, kelompok pertemuan,
dan kelompok penyadar.Sedangkan kelompok
preskriptif mengacu pada langkah-langkah
yang harus ditempuh anggota kelompok
dalam mencapai tujuan kelompok.
Komunikasi kelompok dibedakan atas
dua karakteristik (Effendy, 2003:76).
Komunikasi kelompok kecil dan komunikasi
kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil
ditujukan kepada kognisi komunikan, dan
proses berlangsungnya secara dialogis. Dalam
komunikasi kelompok kecil komunikator
menunjukkan pesannya kepada benak atau
pikiran komunikan, misalnya kuliah, ceramah,
diskusi seminar, rapat dan lain-lain. Dalam
situasi komunikasi seperti ini logika berperan
penting. Komunikan akan dapat menilai logis
tidaknya uraian komunikator. Sementara
komunikasi kelompok besar yang juga disebut
komunikasi publik yang melibatkan banyak
khalayak yang relatif besar, dan karenanya
sulit saling mengenal secara dalam satu
persatu. Para komunikan biasanya berkumpul
diwaktu dan tempat yang sama, misalnya di
auditorium, aula, mesjid, lapangan terbuka
dan lain-lain. Contohnya komunikasi publik
adalah kampanye, rapat akbar, tabligh akbar,
kuliah umum dan sejenisnya.
4. Pengaruh Kelompok pada Perilaku
Komunikasi
Menurut Rakhmat (1994:50), pengaruh
kelompok terhadap perilaku komunikasi
anggotanya, terdiridari : (1) Komformitas,
adalah perubahan perilaku atau kepercayaan
menuju (norma) kelompok, sebagai akibat
tekanan kelompok yang real atau
dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam
kelompok mengatakan atau melakukan
sesuatu, ada kecenderungan para anggota
untuk mengatakan dan melakukan hal yang
sama. (2) Fasilitasi Sosial, adalah kelancaran
atau peningkatan kualitas kerja karena
ditonton kelompok.Kelompok mempengaruhi
pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah.
Dalam hal ini, kehadiran orang lain dianggap
menimbulkan efek pembangkit energy pada
perilaku individu. (3) Polarisasi, adalah
kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim.
Bila sebelum diskusi kelompok para anggota
mempunyai sikap agak mendukung tindakan
tertentu, setalah diskusi mereka akan lebih
kuat lagi mendukung tindakan itu.
Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota
kelompok agak menentang tindakan tertentu,
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 64
setelah diskusi mereka akan menentang lebih
keras.
5. Pengertian Iklim Komunikasi
Menurut Muhammad (2004:85) bahwa ada
hubungan yang sirkuler antara iklim
kelompok dan iklim komunikasi. Tingkah
laku komunikasi mengarahkan pada
perkembangan iklim, diantaranya iklim
komunikasi. Iklim komunikasi dipengaruhi
oleh bermacam-macam cara anggota
kelompok bertingkah laku dan
berkomunikasi. Iklim komunikasi yang penuh
persaudaraan mendorong para anggota
kelompok berkomunikasi, secara terbuka,
rileks, ramah tamah dengan anggota yang
lain. Sedangkan, iklim yang negatif
menjadikan anggota tidak berani
berkomunikasi secara terbuka dan tidak
penuh rasa persaudaraan.
Menurut Redding dan Goldhaber (1986)
dalam Muhammad (1995:85) terdapat lima
dimensi penting dalam iklim komunikasi,
yaitu : (1) “Supportiveness”, atau bawahan
mengamati bahwa hubungan komunikasi
mereka dengan atasan membantu mereka
membangun dan menjaga perasaan diri
berharga dan penting. (2) Partisipasi membuat
keputusan. (3) Kepercayaan, dapat dipercaya
dan dapat menyimpan rahasia. (4)
Keterbukaan dan keterusterangan. (5) Tujuan
kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan
kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada
anggota organisasi.
Gibb dalam Muhammad (1995:85) juga
menegaskan bahwa tingkah laku komunikasi
tertentu dari anggota kelompok mengarahkan
kepada iklim supportiveness. Di antara
tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Deskripsi, anggota organisasi
memfokuskan pesan mereka kepada kejadian
yang dapat diamati daripada evaluasi secara
subjektif atau emosional. (2) Orientasi
masalah, anggota organisasi memfokuskan
komunikasi mereka kepada pemecahan
kesulitan mereka secara bersama. (3)
Spontanitas, anggota organisasi
berkomunikasi dengan sopan dalam berespon
terhadap situasi yang terjadi. (4) “Empathi”,
anggota organisasi memperlihatkan perhatian
dan pengertian terhadap anggota lainnya. (5)
Kesamaan, anggota organisasi
memperlakukan anggota yang lain sebagai
teman dan tidak menekankan kepada
kedudukan dan kekuasaan. (6)
“Provisionalism”, anggota organisasi bersifat
fleksibel dan menyesuaikan diri pada situasi
komunikasi yang berbeda-beda.
Pace et.al, dalam Kriyantono (2006:122)
mengemukakan bahwa iklim komunikasi
adalah persepsi mengenai seberapa jauh
anggota kelompok merasa bahwa kelompok
dapat dipercaya, mendukung, terbuka
terhadap, menaruh perhatian kepada, dan
secara aktif meminta pendapat mereka, serta
memberi penghargaan atas standar kinerja
yang baik. Pace et.al, juga mengatakan bahwa
iklim komunikasi organisasi terdiri dari
persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi
dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap
komunikasi.Adanya iklim komunikasi, juga
dapat menunjukkan kepada anggota
kelompok, bahwa kelompok tersebut
mempercayai mereka dan memberi kebebasan
untuk mengambil keputusan.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 65
Dennis dalam Muhammad (2004:85)
mengemukakan bahwa “iklim komunikasi
sebagai kualitas pengalaman yang bersifat
objektif mengenai lingkungan internal
kelompok, yang mencakup persepsi anggota
kelompok terhadap pesan dan hubungan
pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam
kelompok, yang terdiri dari supportiveness,
partisipasi pembuatan keputusan,
keterbukaan dan keterusterangan, dan tujuan
penampilan yang tinggi.
Muhammad (2004:86) juga menjelaskan
bahwa yang menjadi pokok persoalan utama
dari iklim komunikasi, adalah : (1) Persepsi
mengenai hubungan komunikasi dalam
kelompok, (2) Persepsi mengenai tersedianya
informasi bagi anggota, (3) Persepsi mengenai
kelompok itu sendiri.
Ukuran iklim komunikasi dalam suatu
organisasi dapat diperoleh melalui persepsi
anggota organisasi mengenai pengaruh
komunikasi itu sendiri. Peterson dan pace
dalam (Hastasari, 2007:65) mengemukakan 6
pengaruh komunikasi yang dapat digunakan
untuk mengukur iklim komunikasi tersebut,
yaitu : (1) Kepercayaan, Personel di semua
tingkat harus bekerja keras untuk
mengembangkan dan mempertahankan
hubungan yang didalamnya kepercayaan,
keyakinan dan kualitas didukung oleh
pernyataan dan tindakan. (2) Pembuatan
Keputusan Bersama, Para pegawai disemua
tingkat dalam organisasi harus diajak
berkomunikasi dan berkonsultasi mengenal
semua masalah dalam semua wilayah
organisasi yang relevan dengan kedudukan
mereka. Para pegawai di semua tingkat harus
diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan
berkonsultasi dengan manajemen di atas
mereka agar berperan serta dalam proses
pembuatan keputusan dan penentuan tujuan.
(3) Kejujuran, Suasana umum yang diliputi
kejujuran dan keterusterangan harus
mewarnai hubungan-hubungan dalam
organisasi, dan para pegawai mampu
mengatakan “apa yang ada di dalam pikiran
mereka” tanpa mengindahkan apakah mereka
berbicara kepada teman sejawat, bawahan dan
atasan. (4) Keterbukaan dalam komunikasi
kebawah, Kecuali untuk keperluan rahasia,
anggota organisasi harus relatif mudah
memperoleh informasi yang berhubungan
langsung dengan tugas mereka saat itu, yang
mempengaruhi kemampuan mereka untuk
mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan
orang-orang dan bagian lainnya yang
berhubungan luas dengan perusahaan,
organisasi para pemimpin dan rencana-
rencana. (5) Mendengarkan dalam komunikasi
ke atas, Personel di setiap tingkat dalam
organisasi harus mendengarkan saran-saran
atau laporan-laporan masalah yang
ditemukan personel di setiap tingkat bawahan
dalam organisasi, secara berkesinambungan
dan dengan pikiran terbuka. Informasi dari
bawahan harus dipandang cukup penting
untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang
berlawanan. (6) Perhatian pada tujuan-tujuan
kinerja tinggi, Personel di semua tingkat
dalam organisasi harus menunjukkan suatu
komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja
tinggi, biaya rendah kemudian menunjukkan
perhatian besar pada anggota organisasi
lainnya.
C. METODE PENELITIAN
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 66
Tipe penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini
adalah untuk membuat pecandraan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah
tertentu (Suryabrata, 2011:75). Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian, misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
lain-lain (Kriyantono, 2006:69).
Dalam penelitian ini, peneliti melihat
bagaimana penyampaian nilai-nilai kesadaran
diri dalam melakukan aktivitas komunitas
untuk para anggota dan bagaimana
mempertahankan nilai-nilai tersebut.
Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini
berlaku. Di dalamnya terdapat upaya
mendeskripsikan, mencatat, analisis dan
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang
sekarang ini yang terjadi atau ada (Mardalis,
2010:26)
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan penelitian di
komunitas Trashbag Palu selama 3 bulan,
peneliti telah mengumpulkan data melalui
observasi partisipan yaitu dengan ikut serta
mulai dari rapat pembentukan panitia, rapat
persiapan, pada saar aksi di kegiatan Sapu
Jagad 2017, sampai pada saat penyusunan
laporan pertanggungg jawaban, wawancara
dengan informan yang sudah di tentukan
kategorinya, dan mengkaji literatur-literatur
yang ada kaitannya dengan objek atau
permasalahan yang diteliti. Data yang
diperoleh tersebut, meliputi iklim komunikasi
yang terjadi pada komunitas Trashbag Palu.
Untuk memudahkan dalam interpretasi data,
peneliti menguraikan data tersebut secara
sistematis, memilah hasil wawancara sesuai
dengan lima dimensi yang di pakai sebagai
teori dasar dalam penelitian ini, peneliti juga
menganalisa jenis komunikasi yang
berlangsung dalam komunitas Trashbag, jenis
komunikasi tersebut adalah komunikasi
vertikal dan komunikasi horizontal.
Pada penelitian ini, peneliti melakukan
penelitian pada Trashbag Palu ketika mereka
sedang mempersiapkan kegiatan Sapu Jagad
2017 mulai dari rapat persiapan pada bulan
Mei sampai pada hari kegiatan tanggal 16
Agustus dan pasca kegiatan untuk membuat
laporan pertanggung jawaban. Sapu Jagad
adalah agenda rutin tahunan yang di lakukan
Trashbag Pusat dan bekerja sama dengan
Pengurus Trashbag di beberapa daerah yang
gunungnya di pilih sebagai gunung yang
akandibersihkan. Agenda kegiatan Sapu Jagad
berupa membersihkan gunung di jalur
pendakian, melakukan upacara bendera di
puncak pendakian, membawa turun sampah
yang sudah dikumpulkan, lalu mensortir
jenis-jenis sampah, dan membuang sampah di
tempat pembuangan akhir.
Pada proses komunikasi yang terjadi di
saat perkenalan diri satu persatu termasuk
komunikasi atasan ke bawahan (downward
communication), komunikasi bawahan ke
atasan (upward communication), komunikasi
horizontal (horizontal communication),dan
komunikasi lintas saluran (inuterline
communication). Karena pada saat proses
perkenalan diri semua semua elemen
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 67
melakukan komunikasi dan mendapat
tanggapan atau feedback.
Adapun hasil yang dikumpulkan oleh
peneliti melalui wawancara dan observsi
partisipan adalah sebagai berikut :
(a) Supportiveness atau saling mendukung
Hubungan komunikasi merupakan hal
yang penting dalam kelompok, karena tanpa
adanya komunikasi dapat mengakibatkan
suatu kelompok tidak berjalan seperti
seharusnya, maksudnya adalah tidak
mengikuti peraturan kelompok, pengambilan
keputusan dilakukan secara sepihak tanpa
mendiskusikannya terlebih dahulu, anggota
kelompok cenderung bergerak sendiri tanpa
adanya koordinasi sesama anggota,
sebagaimana yang dikatakan oleh Pater
(Ketua Trashbag) yaitu :
“Sebagai seorang yang dipercaya
menjadi ketua Trashbag community
DDP Sulteng saya menempatkan diri
sesuai porsi dan tugas saya sebagai
ketua untuk merangkul dan
menyatukan pemahaman masing-
masing anggota yang berbeda-beda
pemikiran dan karakter”(Wawancara
Secara Online Tanggal 30 Oktober
2017)
Saling mendukung dapat di tunjukkan
dengan cara perilaku dan kata-kata, salah satu
contoh saling mendukung yang di tunjukkan
oleh ketua Pater sebagai Ketua Trashbag yaitu
:
“Saya mendukung anggota Trashbag
untuk melakukan aksi apapun, selama
itu terkait dengan pembersihan
sampah. Saya membantu mereka
berkoordinasi dengan Trashbag pusat
dan membantu penyaluran
perlengkapan aksi pembersihan
sampah”.
Ketika pada saat berlangsungnya kegiatan
atau pada saat akan melakukan aksi, biasanya
terdapat beberapa masalah. Disinilah tugas
seorang ketua di butuhkan sebagai penengah
untuk mencari jalan keluar. Menurut hasil
wawancara dengan Pater (Ketua Trashbag),
bahwa :
“Cara saya dalam mengambil
keputusan adalah dengan melakukan
kesepakatan bersama dengan
pengurus dan seluruh anggota baik
itu dalam rapat ataupun dilapangan.
Dalam musyawarah saya sendiri
menerapkan untuk seluruh anggota
agar dapat meyuarakan pendapat atau
idenya sendiri” ”(Wawancara Secara
Online Tanggal 30 Oktober 2017)
Ketika keputusan sudah di sepakati
bersama untuk menjalankan keputusan itu
perlu adanya dukungan dari Ketua dan
Pengurus. Dalam hal ini, dukungan di
butuhkan untuk memaksimalkan kinerja
anggota dalam menjalankan tugas masing-
masing sesuai keputusan yang telah di
sepakati bersama. Seperti yang di katakan oleh
Sham selaku Ketua Panitia Sapu Jagad 2017,
bahwa :
“Setelah menyepakati keputusan
bersama-sama, saya selalu
memberikan dukungan pada setiap
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 68
panitia agar tugas mereka bisa
maksimal sesuai dengan porsi masing-
masing, saya memberikan dukungan
kepada mereka dengan selalu
mengingatkan apa tugas mereka dan
selalu mengawasi agar tugas mereka
optimal” (Wawancara 23 Oktober
2017)
Saling mendukung tidak hanya
ditunjukkan oleh Ketua Trashbag dan Ketua
Panitia Sapu Jagad, anggota juga
menunjukkan saling mendukungnya melalui
kata-kata. Seperti yang dikatakan oleh Faisal
sebagai Koordidantor Bidang Logistik :
Saya mendukung anggota-anggota
Trashbag untuk melakukan aksi, saya
biasanya bertanya apakah mereka sudah
menyelesaikan tugas yang diberikan, ketika
ada hambatan saya memberikan solusi kepada
mereka, jika yang mereka butuhkan adalah
peralatan untuk tugas mereka saya langsung
mengkomunikasikan kepada Ketua Trashbag
agar Trashbag Pusat dapat menyiapkan
peralatan yang dibutuhkan. (Wawancara 24
Oktober 2017)
(b) Partisipasi
Partisipasi atau keikutsertaan yang
dilakukan oleh anggota Trashbag murni
karena kerelaan dan tidak ada paksaan dari
pihak manapun. Mereka ikut bergabung di
Trashbag karena tertarik untuk membersihkan
sampah yang ada pada gunung dan hutan di
Sulawesi Tengah. Partisipasi yang dilakukan
oleh anggota terlihat pada saat rapat.
Dengan partisipasi yang penuh dan
komunikasi yang lancar, maka ketika
menghadapi masalah akan terasa lebih
mudah. Seperti pendapat Faisal (Koordinator
Bidang Logistik) yaitu :
“Karena komunikasi menjadi
penggerak suatu komunitas, jadi saya
rasa sangat penting untuk menjaga
agar tetap mempunyai hubungan
yang baik satu sama lain, supaya
kalau ada masalah penyelesaiannya
tidak memakan waktu yang lama, yah
karena semua satu pikiran”
(Wawancara 24 Oktober 2017)
Komunikasi yang terjalin memiliki
peranan penting dalam kelompok, karena
setiap opini, masukan, dan kritikan oleh
anggota merupakan sumber untuk bagaimana
terus memperbarui kelompok tersebut.
Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik,
maka para anggota akan berpartisipasi dengan
sukarela tanpa harus ada paksaan. Ketika para
anggota berpartsipasi dalam tekanan atau ada
paksaan maka hasil kerja mereka tidak akan
maksimal. Berpartisipasi dalam sebuah
kelompok haruslah bersungguh-sungguh,
agar apa yang menjadi tujuan kelompok
tersebut bisa tercapai.
Peneliti juga melihat bahwa semua
anggota bergabung dengan sukarela tanpa
adanya paksaan atau tekanan.Walaupun ada
sebagian anggota bergabung bukan karena
kemauan sendiri, mereka bergabung atas
ajakan dari teman. Hal ini dibenarkan oleh
Eka (Sekretaris Trashbag) yaitu :
“Saya bersyukur mereka bergabung di
Trashbag secara sukarela dan
mempunyai visi yang sama, yaitu
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 69
sama-sama ingin menjaga kebersihan
gunung dari sampah-sampah yang
dihasilkan oleh penggiat alam yang
tidak bertanggung jawab”(Wawancara
24 Oktober 2017)
Hal tersebut juga di benarkan oleh
Ramadhan (Sukarelawan Sapu Jagad 2017),
yaitu :
“Saya mengikuti kegiatan di Trashbag
dengan sukarela, karena tertarik
dengan tujuan Trashbag walaupun
saya mengetahui Trashbag hanya dari
teman”(Wawancara 24 Oktober 2017)
(c) Kepercayaan
Setelah hubungan komunikasi dibangun
dan dijaga, pastilah akan menumbuhkan rasa
percaya pada masing-masing orang yang
melakukan komunikasi tersebut. Rasa percaya
akan terbangun seiring dengan seringnya
komunikasi dilakukan oleh setiap anggota.
Mariana (Sukarelawan Sapu Jagad 2017)
berpendapat bahwa :
“Saya memang bergabung di
Trashbag karena ajakan dari teman
saya, tapi setelah bergabung dan
masih menjalin komunikasi pasca
kegiatan, saya sudah menaruh rasa
percaya dengan mereka
(anggota/sukarelawan Trashbag)
karena sudah sering berkomunikasi
bahkan sering bertemu”(Wawancara
30 Oktober 2017)
Selama penelitian berlangsung peneliti
menemukan bahwa, ada beberapa anggota
Trashbag yang kurang aktif menjalin
komunikasi yang berbeda latar belakang
organisasi. Hal ini juga membuat mereka
kurang membuka diri kepada anggota lain
yang berbeda latar belakang. Hal ini
dibenarkan oleh Ramadhan (Sukarelawan
Sapu Jagad 2015) bahwa :
“Saya tidak menutup diri dari semua
jenis komunikasi yang ada, tapi saya
lebih nyaman berkomunikasi dengan
anggota Trashbag yang sama latar
belakangnya dengan saya (satu
jurusan di kampus) karena kami
sering bertemu dikampus jadi topik
pembicaraan tidak akan melenceng
jauh”(Wawancara 30 Oktober 2017)
Komunikasi yang bersifat terbuka
sangatlah penting, karena dapat membantu
para anggota menyampaikanapa yang ada
dipikiran mereka berupa ide, gagasan, kritik
dan saran. Ketika terjadi konflik akan mudah
mengetahui bagaimana cara mengatasinya.
Menurut hasil wawancara dengan Eka
(Sekretaris Trashbag) yaitu :
“Setiap orang jika ingin bergabung di
sebuah komunitas harus siap untuk
terbuka, tapi yang bersangkutan
dengan komunitas. Jika saya
mempunyai masalah di dalam
komunitas, saya akan
menyelesaikannya dengan
menanyakan langsung pada orang
yang bersinggungan dengan saya,
supaya tidak merembet”(Wawancara
24 Oktober 2017)
Lalu Eka juga menambahkan bahwa :
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 70
“Saya rasa semua orang yang ada di
Trashbag sudah mengetahui
bagaimana seharusnya menyelesaikan
masalah dalam komunitas, karena
mereka semua rata-rata bergabung di
sebuah organisasi sebelum Trashbag,
sampai sekarang saya merasa mereka
terbuka dalam segala hal menyangkut
komunitas (kecuali urusan
pribadi)”(Wawancara 24 Oktober
2017)
(d) Keterbukaan
Dengan komunikasi terbuka yang terus
berlangsung maka semakin lama anggota
akan merasa mempunyai kedekatan
emosional dengan anggota lainnya. Seperti
yang dikatakan oleh Faisal (Koordinator
Bidang Logistik) bahwa :
“Ketika saya menjalankan tugas saya,
pastinya saya harus mengenal semua
anggota karena sayalah yang
mengurus dan menyiapkan
kebutuhan mereka pada saat di
lapangan. Saya akan merasa dekat
dengan anggota yang sering
berkomunikasi dengan saya bahkan
saking seringnya kadang tanpa
mereka memberi tahu saya sudah bisa
memperkirakan apa kebutuhan
mereka”(Wawancara 24 Oktober 2017)
Dari penjelasan di atas dapat di ketahui
bahwa komunikasi yang bersifat terbuka akan
sangat membantu dalam menjalankan
aktivitas komunitas. Apalagi mengingat
Trashbag adalah komunitas yang hampir
semua kegiatannya merupakan kegiatan luar
ruangan. Setiap kelompok atau komunitas
pasti mempunyai tujuan masing-masing,
untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kerja
sama seluruh anggota guna tercapainya tujuan
tersebut. Kerja sama yang dibutuhkan mulai
dari komunikasi yang harus selalu terjaga,
tingginya partisipasi dalam setiap kegiatan,
ketika ada konflik harus bisa menyamakan
pikiran agar mendapat solusi yang tepat,
sampai dengan loyalitas terhadap komunitas
walaupun sedang dalam masalah.
(e) Tujuan Kinerja yang Tinggi
Adanya tujuan dalam komunitas menjadi
penggerak agar seluruh anggota tetap
semangat untuk mencapainya. Jika seluruh
anggota sadar dengan hak dan kewajibannya,
tujuan komunitas akan tercapai. Tetapi, dalam
sebuah komunitas pastilah menemukan
halangan.Apalagi Trashbag merupakan
komunitas peduli lingkungan dan
beranggotakan orang-orang yang memiliki
latar belakang berbeda-beda. Seperti yang di
katakan oleh Eka (Sekretaris Trashbag) yaitu :
“Trashbag ini adalah komunitas
nonprofit, jadi pasti orang yang
bergabung sudah bisa
mengesampingkan keuntungan.Tapi
namanya saja manusia pasti
mempunyai pikiran dan pendapat
yang berbeda-beda. Saya sebagai
sekretaris sejauh ini bersyukur karena
semua anggota Trashbag adalah
orang-orang yang mempunyai
kesadaran diri yang
tinggi”(Wawancara 24 Oktober 2017)
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 71
Menurut data yang peneliti dapatkan,
bahwa di Trashbag tidak memberlakukan
sistem NRA (Nomor Registrasi) seperti yang
biasa di terapkan pada komunitas peduli
lingkungan lainnya.Jadi, hal ini membuat para
anggota leluasa mengeluarkan pendapat
mereka tanpa harus takut dimarahi senior
mereka. Hal ini dibenarkan oleh Faisal
(Koordinator Bidang Logistik), bahwa :“Di
Trashbag saya merasa lebih fleksibel, karena
tidak memandang umur, titel atau jabatan,
semuanya sama. Jadi saya merasa lebih santai
karena ketika saya ingin menyampaikan
pikiran saya tidak harus menunggu diberikan
kesempatan dan tidak takut dimarahi
senior”(Wawancara 24 Oktober 2017)
Sistem yang fleksibel membuat anggota
Trashbag menjadi lebih mudah dalam
beraksi.Karena mengingat Trashbag adalah
komunitas peduli lingkungan non-profit, jadi
semua anggota secara sukarela meluangkan
waktu, pikiran, tenaga dan materi.Dengan
sistem yang fleksibel juga membuat para
anggota jadi lebih terbuka dan tidak menutup
diri.Menurut hasil wawancara, semua
informan mengatakan bahwa karena Trashbag
fleksibel mereka membuka semua peluang
komunikasi mulai dari komunikasi langsung
ataupun melalui media. Hal ini juga
dibenarkan oleh Pater (Ketua Trashbag)
bahwa :
“Syukurnya, mereka semua aktif
berkomunikasi dengan saya selaku
ketua. Karena saya sering di luar kota
jadi saya sangat membuka peluang
untuk berkomunikasi via medsos.
Walaupun saya jauh saya tetap
mengingatkan mereka melakukan
aksi, tetap memberi pembinaan, dan
selalu mengawasi perkembangan
yang ada”(Wawancara secara Online
tanggal 30 Oktober 2017)
Berkomunikasi merupakan kebutuhan
dasar manusia. Dengan berkomunikasi
manusia dapat saling berhubungan satu sama
lain, mulai dari kehidupan sehari-hari,
kehidupan rumah tangga, di tempat kerja, dan
dimana saja manusia itu berada. Dengan
adanya komunikasi yang baik dalam suatu
kelompok, segala aktivitas kelompok dapat
dilaksanakan dengan mudah dan lancar.
Begitu pula sebaliknya, jika komunikasi dalam
suatu kelompok kurang baik maka
pelaksanaan aktivitas kelompok akan
terhambat. Menurut John Oetzel dalam
Littlejohn and Foss (2008:335) bahwa
kemampuan untuk berkomunikasi secara
efektif dengan orang dari latar belakang yang
berbeda di tempat kerja dalam dunia
globalisasi. Akan tetapi, apa yang dimaksud
dengan berkomunikasi secara efektif harus
diputuskan dalam standar adil dan tepat bagi
semua kebudayaan, tidak hanya budaya
mayoritas. Keefektifan organisasi bergantung
pada tingkatan yang memberikan manajemen
kekuasaan resmi (legitimate power) oleh
organisasi.
Idealnya suatu organisasi adalah memiliki
hubungan yang baik antar sesama anggota.
Terciptanya hubungan yang baik antar sesama
anggota adalah hasil dari proses komunikasi
berjalan lancar. Hubungan yang baik meliputi
saling menghargai, saling memberikan
kesempatan dan saling percaya. Baiknya
komunikasi dalam organisasi tidaklah bisa
hanya dilakukan oleh seorang ketua saja,
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 72
melainkan seluruh elemen yang ada di dalam
kelompok tersebut. Oleh karena itu seluruh
anggota di tuntut agar dapat menjaga
komunikasi kelompok dengan baik, mulai dari
komunikasi antara ketua pada anggota,
anggota pada ketua, sampai komunikasi
sesama anggota. Menurut Karl Weick dalam
Littlejohn and Foss (2008:365) bahwa Kegiatan
berorganisasi berfungsi untuk mengurangi
ketidakpastian informasi.
Kelompok memiliki banyak bidang
didalamnya, semuanya sudah menempati
posisi dan dengan tugasnya masing-
masing.Hal ini merupakan struktur yang
kompleks, maka untuk mengatur dan
mempersatukannya diperlukan komunikasi
dan ditunjang oleh iklim komunikasi yang
baik.Jika komunikasi berjalan dengan baik
maka iklim komunikasi dalam suatu
kelompok pastilah berjalan dengan lancar. Hal
tersebut akan membuat tujuan suatu
kelompok bisa tercapai dengan dukungan
komunikasi dan iklim komunikasi yang baik.
Menurut Bales dalam Littlejohn and Foss
(2008:327) bahwa posisi individu dalam
sebuah kelompok adalah sebuah fungsi dari
tiga dimensi: (1) dominan lawan pasif; (2)
ramah lawan tidak ramah; (3) aktif lawan
emosional. Dalam sebuah kelompok tertentu,
perilaku anggota dapat ditempatkan pada
ketiga dimensi ini. Posisi individu juga
bergantung bagaimana sifat dan perilakunya
ketika beraktivitas dalam kelompok.
Iklim komunikasi sering dikaitkan dengan
konteks kelompok yang menggerakkan
banyak individu didalamnya.Tingkah laku
komunikasi para anggota mengarah pada
perkembangan iklim, diantaranya iklim
kelompok. Iklim komunikasi dipengaruhi oleh
banyak faktor, salah satunya adalah tingkah
laku anggota dalam kelompok dan bagaimana
mereka berkomunikasi serta keinginan dan
kesempatan bagi perkembangan kelompok
tersebut.Iklim bukanlah sifat yang individual,
tetapi sifat yang dibentuk, dimiliki bersama
dan dipelihara oleh semua anggota
kelompok.Berbicara masalah iklim
komunikasi, tentu saja melibatkan kepuasan
dalam berkelompok. Kepuasan berkelompok
dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan
anggota, seperti informasi mengenai apa-apa
saja yang akan dilakukan, berita terbaru
tentang kelompok, terutama informasi yang
berkaitan dengan tugas mereka. Dengan
tersebarnya arus informasi yang mengalir
secara merata, maka seluruh anggota
kelompok dapat mengetahui perkembangan
yang ada.
Iklim komunikasi dibentuk melalui
interaksi antaranggota kelompok. Pandangan
seseorang yang subjektif menyatakan bahwa
interaksi-interaksi dan proses-proses yang
menciptakan kembali, mengubah, dan
memelihara iklim adalah hal-hal yang
seharusnya menjadi pusat perhatian bukannya
respon setiap individu atau respon total di
dalam suatu kelompok. Contohnya menjaga
proses komunikasi antar anggota berjalan
dengan lancar. Menurut perspektif subjektif,
interaksi adalah hal yang paling penting
untuk perkembangan iklim.
Iklim komunikasi merupakan gabungan
dari persepsi-persepsi, suatu evaluasi, dan
mengenai peristiwa komunikasi, perilaku dan
respon, harapan-harapan, konflik-konflik
antarpersonal, dan kesempatan bagi
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 73
pertumbuhan dalam kelompok tersebut.Iklim
komunikasi kelompok terdiri dari persepsi-
persepsi atas unsure-unsur organisasi dan
pengaruh unsur-unsur terhadap
komunikasi.Pengaruh ini didefinisikan,
disepakati, dikembangkan, dan dikokohkan
secara berlanjut, melalui interaksi dengan
anggota kelompok.Pengaruh ini menghasilkan
pedoman bagi keputusan-keputusan dan
tindakan-tindakan individu, dan
mempengaruhi pesan-pesan mengenai
kelompok.
Selain itu, ikim komunikasi juga berfungsi
untuk menunjukkan kepada anggota
kelompok bahwa kelompok tersebut
mempercayai mereka dan memberi kebebasan
dalam mengambil resiko (keputusan),
mendorong anggota kelompok dan memberi
mereka tanggung jawab dalam mengerjakan
tugas-tugas mereka; menyediakan informasi
yang terbuka dan cukup tentang kelompok;
mendengarkan dengan penuh perhatian serta
memperoleh informasi yang dapat dipercayai
dan terus terang dari anggota kelompok;
secara aktif memberi penyuluhan kepada para
anggota kelompok; sehingga mereka dapat
melihat bahwa keterlibatan mereka penting
bagi keputusan-keputusan dalam kelompok;
dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang
bermutu tinggi dan memberi tantangan.
Komunikasi akan dapat dilaksanakan
dengan lebih baik, apabila seluruh anggota
kelompok dan ketua, dapat melaksanakan
komunikasi dengan efektif, maka banyak
manfaat yang dapat diambil, misalnya
kelancaran tugas dapat lebih terjamin. Salah
satu upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan komunikasi kelompok, selain
menjalankan komunikasi formal yang
dijalankan oleh seorang anggota kelompok,
komunikasi informalpun wajib dilakukan
untuk mendapat umpan balik dari para
anggota.Agar komunikasi dalam kelompok
berfungsi dengan baik, maka penyampaian
pesan itu harus sebagaimana mestinya dan
tidak direkayasa. Apabila isi pesan tersebut,
disampaikan tidak sebagaimana mestinya dan
ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan,
maka harus segera diketahui, dan selanjutnya
diperbaiki bersama untuk kemajuan
kelompok. Sebaliknya, apabila suatu pesan
disampaikan tidak sebagaimana mestinya,
maka akan menimbulkan hambatan
komunikasi dalam kelompok, dan hal ini tentu
saja akan mempengaruhi iklim komunikasi.
Iklim komunikasi yang terjadi pada
komunitas Trashbag Palu merupakan sebuah
proses komunikasi yang terjadi antara ketua
Trashbag Palu dengan sukarelawannya,
sesama anggota Trashbag Palu, ketua panitia
Sapu Jagad dengan susunan
kepanitiaannya,dan panitia dengan anggota
Trashbag Palu. Pola komunikasi yang ada
pada Trashbag Palu berupa penyampaian ide,
gagasan, informasi, opini, serta hal-hal yang
muncul dari anggota Trashbag Palu.
Selanjutnya anggota Trashbag Palu dan
panitia Sapu Jagad akan mendapatkan respon
atau tanggapan dari para ketua untuk
dijadikan bahan pertimbangan dan masukan
bagi kelompok dan panitia. Respon yang
diberikan merupakan tanggapan yang positif
dari ketua Trashbag Palu dan ketua Panitia
Sapu Jagad, dan juga adanya keterbukaan
untuk mau menerima masukan dan kritikan
dari setiap anggotanya merupakan faktor
yang terpenting dalam membangun sebuah
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 74
komunikasi. Di dalam kelompok terdapat lima
dimensi yang dapat mengukur bagaimana
perkembangan iklim komunikasi kelompok
tersebut, yaitu :
Dengan berdasarkan hasil penelitian
tersebut, peneliti melihat iklim komunikasi di
komunitas Trashbag Palu. Bahwa dari semua
lima dimensi yang dipakai untuk melihat
bagaimana pola komunikasi yang terbangun
didalam komunitas, peneliti menemunkan
bahwa disetiap kegiatan Trashbag mulai
sekedar kumpul, rapat formal, rapat informal,
sosialisasi, dan sampai aksi bahwa iklim
komunikasi di Trashbag Palu dapat dilihat
dengan 4 jenis komunikasi organisasi menurut
Pace and Fules: (1) komunikasi atasan ke
bawahan (downward communication); (2)
.komunikasi bawahan ke atasan (upward
communication); (3) komunikasi horizontal
(horizontal communication); dan (4)
komunikasi lintas saluran (interline
communication).
Selanjutnya peneliti akan membahas
bagaimana iklim komunikasi yang terjadi
pada Trashbag Palu.
(a) Supportiveness atau saling mendukung
Adalah proses komunikasi yang membuat
anggota kelompok merasa penting dan
mengapresiasi dalam bentuk apapun. Dalam
komunikasi horisontal yang terjalin di
Trashbag terdapat dimensi supportiveness,
menurut data yang di temukan oleh peneliti
adalah dengan datang mengikuti rapat adalah
bentuk saling mendukung terhadap sesama
anggota, saling mengingatkan untuk datang
rapat, ketika pada saat rapat menghormati
orang yang sedang berbicara mengatakan ide,
saran dan kritik.
Berdasarkan observasi partisipan yang
peneliti lakukan pada saat rapat pertama yang
membahas tentang perkenalan sesama
anggota, dalam rapat itu beberapa anggota
sudah mulai mengeluarkan
pendapatnya.Seperti pada saat Sham selaku
ketua panitia Sapu Jagad 2017 memberikan
kesempatan pada peneliti untuk
memperkenalkan diri kepada anggota-
anggota lainnya dan mereka merespon
dengan baik. Setelah melakukan perkenalan,
kemudian Sham menyusun nama-nama
anggota dan membagi tugas sesuai
kemampuan dan pengalaman masing-masing.
Ketika pembagian tugas, pada setiap bidang
Sham bertanya kesiapan para anggota dalam
menjalankan tugas. Sham juga memberikan
dukungan dan motivasi terkait aksi yang akan
dilakukan pada bulan Agustus. Sham juga
memberikan penguatan bahwa aksi yang akan
dilakukan murni sukarela. Jadi, yang ingin
terlibat harus memiliki loyalitas yang tinggi.
Rasa saling mendukung kemudian muncul
dari para anggota yang sudah terlebih dahulu
memiliki pengalaman di bidang peduli
lingkungan. Mereka memberikan motivasi
bahwa jika tidak peduli sekarang lalu kapan ?
Berdasarkan hal itulah peneliti menilai bahwa
di Trashbag para anggotanya saling memberi
dukungan agar para anggota tidak ragu untuk
melakukan aksi.
Proses komunikasi terjadi dalam berbagai
cara dan berbagai fungsi, sebelum melakukan
komunikasi orang-orang biasanya
memikirkan untuk apa dia berkomunikasi. Di
dalam organisasi hal-hal yang
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 75
dikomunikasikan biasanya berupa ide atau
gagagasan, masukan dan kritikan, ungkapan
perasaan, atau sekedar basa-basi. Didalam
organisasi saling mendukung adalah hal yang
penting, karena setiap anggota organisasiakan
merasa dihargai ketika keputusan yang dia
ambil didukung sepenuhnya oleh anggota
kelompok lainnya. Bentuk dukungan juga
bermacam-macam, mulai dari dukungan
mental sampai dukungan materi. Dukungan
mental biasanya dilakukan pada saat
pengambilan keputusan sedangkan dukungan
materi dilakukan ketika keputusan sudah
dibuat dan akan merealisasikan keputusan
tersebut.
Dalam berorganisasi rasa saling
mendukung dibutuhkan semua anggota,
khususnya pada ketua terhadap anggotanya.
Karena jika seluruh anggota mendapat
dukungan penuh dari ketua maka ketika
mereka bertindak atau melakukan aktivitas
organisasi mereka akan merasa bahwa mereka
juga mendapat perhatian dari ketua, dan itu
sudah seharusnya terjadi. Apabila anggota
kelompok tidak mendapat dukungan dari
ketua atau dari anggota lainnya mereka akan
merasa bahwa yang mereka lakukan sia-sia
dan tidak berguna. Mengingat status
keanggotaan Trashbag Palu yang banyak
mengandalkan bantuan sukarelawan maka
peran ketua dalam hal mengkoordinir dan
bagaimana ketua mampu meyakinkan pada
seluruh anggota termasuk sukarelawan untuk
tetap perduli terhadap lingkungan. Rasa
saling mendukung juga harus
dikomunikasikan dengan cara yang baik,
karena dengan cara berkomunikasi yang baik
dapat membantu anggota organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi tersebut.
Dalam konteks mengenai terpenuhinya
rasa saling mendukung pada Trashbag Palu
tergantung bagaimana cara penyampaian
yang dilakukan oleh sesama anggota. Dalam
dunia pekerjaan, kita mengenal komunikasi
vertikal dan komunikasi horizontal.
Komunikasi vertikal yang terjadi pada atasan
ke bawahan, komunikasi yang berlangsung
dapat berbentuk penyampaian informasi,
pesan ataupun instruksi kerja yang diberikan.
Sedangkan komunikasi horizontal yang terjadi
pada bawahan ke atasan, komunikasi yang
berlangsung dapat berbentuk tanggapan, ide,
saran ataupun kritik. Secara otomatis, jika 2
jenis komunikasi tersebut berjalan dengan
lancar maka hubungan antara atasan-bawahan
dan bawahan-atasan dapat berlangsung
dengan baik. Jika komunikasi sudah berjalan
dengan baik, maka akan terbentuk kedekatan
secara emosional yang menciptakan rasa
saling mendukung untuk melakukan aktivitas
komunitas.
Melihat perilaku para anggota Trashbag
yang memilki rasa saling mendukung yang
cukup tinggi, bisa dikatakan dimensi
supportiveness di Trashbag dapat dikatakan
sangat baik.
(b) Partisipasi
Adalah tindakan anggota kelompok untuk
ikut serta dalam aktifitas kelompok tersebut.
Menurut data yang peneliti dapatkan, dimensi
partisipasi pada iklim komunikasi yang terjadi
di Trashbag Palu berupa tindakan pengurus
dan sukarelawan yang mau datang untuk
rapat, mulai dari rapat persiapan ke-1 sampai
dengan rapat final check bersama Balai Besar
Taman Nasional Lore Lindu selaku pihak
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 76
yang bekerja sama untuk melaksanakan
kegiatan Sapu Jagad. Selain datang pada saat
rapat, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh
pengurus inti dan sukarelawan juga di
tunjukkan berupa, datang pada saat sosialisasi
dan Kopi Darat di Café Om Dokter Talise
pada tanggal 22 Juni 2017. Jumlah orang yang
datang pada kegiatan tersebut adalah 18
orang.
Tingkat partisipasi anggota pada kegiatan
Sapu Jagad bisa di bilang cukup tinggi karena
setiap di adakan rapat anggota banyak yang
hadir seperti pada tabel 4.1. tingkat partisipasi
anggota semakin lama semakin bertambah
seiring dengan semakin dekatnya hari
kegiatan Sapu Jagad 2017.Mereka juga
menunjukkan partisipasi mereka bukan hanya
sekedar hadir pada saat rapat saja, tetapi
mereka menjalankan tugas-tugas mereka
dengan sungguh-sungguh agar kegiatan yang
persiapakan berjalan dengan lancar.Dalam
berorganisasi setiap individu dapat
berinteraksi dengan semua struktur yang
terkait baik itu secara langsung maupun
secara tidak langsung kepada organisasi yang
mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara
efektif setiap individu bisa berpartisipasi pada
organisasi yang bersangkutan. Dengan
berpartisipasi setiap individu dapat lebih
mengetahui hal-hal apa saja yang harus
dilakukan.
Pada dasarnya partisipasi didefinisikan
sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan
emosi atau perasaan seseorang di dalam
situasi kelompok yang mendorongnya untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok
dalam usaha mencapai tujuan.Keterlibatan
aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya
berarti keterlibatan jasmaniah semata.
Partisipasi dapat diartikan sebagai
keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau
perasaan seseorang dalam situasi kelompok
yang mendorongnya untuk memberikan
sumbangan kepada kelompok dalam usaha
mencapai tujuan serta turut bertanggung
jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
Menuruth Keith Davis ada tiga unsur
penting partisipasi : (1) Unsur pertama, bahwa
partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya
merupakan suatu keterlibatan mental dan
perasaan, lebih daripada semata-mata atau
hanya keterlibatan secara jasmaniah. Hal ini
berarti keterlibatan di dalam sebuah
organisasi bukan sekedar bantuan tenaga,
tetapi keterlibatan dalam hal mental dan
perasaan. Ketika ada seorang anggota
mendapat masalah anggota lainnya turut
membantu untuk menyelesaikannya. (2)
Unsur kedua adalah kesediaan memberi
sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai
tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat
rasa senang, kesukarelaan untuk membantu
kelompok. (3) Unsur ketiga adalah unsur
tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan
segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.
Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada
rasa “sense of belongingness”.
(c) Kepercayaan
Adalah para anggota harus menjaga
semua hal yang ada didalam komunitas, baik
hal buruk maupun hal baik.Kepercayaan
disini maksudnya, semua anggota harus
percaya pada diri masing-masing dan pada
anggota lainnya bahwa mereka mampu
melaksanakan tugas yang sudah diberikan.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 77
Robert Galford dan Anna Seibold dalam
bukunya The Trusted Leader(2011),
mengatakan terdapat beberapa kategori trust
dalam organisasi: (1) Strategic trust.
Merupakan kepercayaan yang harus dibangun
dan dimiliki organisasi terhadap misi, strategi
dan kemampuan sukses organisasinya.
Ketidakjelasan terhadap hal tersebut akan
memunculkan ketidakjelasan langkah strategis
yang dilakukan organisasi. (2) Organizational
trust. Yakni kepercayaan bahwa kebijakan
organisasi dijalankan dengan adil.
Memberikan ruang bagi person di dalamnya
untuk berkembang secara optimal dan
sistemis. (3) Personal Trust. Yakni
kepercayaan bahwa semua person yang ada
dalam organisasi di drive oleh pemimpin yang
berlaku adil dan peduli terhadap kepentingan
mereka. Para pemimpin harus memiliki
kredibilitas (Credibility) dan pengetahuan
tentang apa yang menjadi tugas
kepemimpinannya. Bisa diandalkan
(Reliability)dan memiliki kedekatan bersama
(Intimacy).
Peneliti melihat bahwa di Trashbag rasa
saling percaya yang terbangun di dalamnya
sudah cukup baik. Karena selama penelitian
berlangsung peneliti melihat semua anggota
Trashbag mendapatkan tugas masing-masing
dan menyelesaikan tugas tersebut mulai dari
rapat pertama sampai dengan penyusunan
laporan setelah kegiatan berakhir.
(d) Keterbukaan
Adalah sifat terbuka yang dimiliki oleh
para anggota yang berguna untuk tetap
konsisten dalam menjalani komitmen yang
disepakati dari awal ketika akan bergabung
didalam kelompok.Keterbukaan juga berarti
bagaimana seseorang menunjukkan kualitas
pribadinya kepada orang lain. Keterbukaan
juga bermakna lebih dari pada sekedar
kualitas pribadi (personal quality), tetapi
merupakan dimensi dari interaksi sosial,
hubungan antar individu dalam kelompok
atau organisasi. Karenanya, keterbukaan
(openness) merupakan kualitas hubungan
antar individu (a character of relationships).
Keterbukaan juga dapat terus
dikembangkan melalui diskusi aktif yang
efektif sehingga dapat terjadi pertukaran
pendapat dan bisa saling mendengar,
memahami dan menerima pemikiran orang
lain dalam kelompok. Bila seseorang dapat
terbuka dalam sebuah kelompok kecil seperti
keluarga, maka pengalaman tersebut bisa
dijadikan sebagai landasan terbangunnya
keterbukaan dalam berorganisasi. Tentunya
bukan hanya satu orang saja yang harus
terbuka ketika berorganisasi, seluruh anggota
juga harus melakukan hal yang sama agar
orang-orang yang ada di dalam organisasi dan
memiliki visi dan misi bersama dapat
mencapai tujuan organisasi tersebut.
Menurut hasil penelitian, keterbukaan
dapat dilihat ketika para anggota mampu
mengeluarkan pendapatnya pada saat rapat
persiapan kegiatan Sapu Jagad 2017. Tetapi
karena di dalam Trashbag beranggotakan
orang-orang dari latar belakang yang berbeda
pula, peneliti melihat beberapa anggota hanya
akan terbuka ketika mereka berbicara dengan
anggota yang latar belakangnya sama. Seperti
mereka yang sama-sama tergabung dalam
sebuah kelompok pencinta alam, cara mereka
berkomunikasi terlihat berbeda. Terlihat
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 78
ketika mereka sedang berbicara mereka
terkadang memakai bahasa yang sedikit kaku
dan tidak sedang dalam keadaan bercanda.
Jadi, peneliti merasa bahwa tingkat
keterbukaan di Trashbag cukup rendah.
(e) Tujuan Kinerja yang Tinggi
Adalah hal yang menggerakkan para
anggota untuk mewujudkannya.Yaitu berupa
visi dan misi yang telah disepakati dan semua
anggota harus berusaha agar tujuan organisasi
tersebut dapat terwujud. Agar tujuan
organisasi dapat terwujud diperlukan kinerja
yang sungguh-sungguh, mulai dari ikut
terlibat di setiap kegiatan organisasi, saling
mendukung satu sama lain, jika sudah saling
mendukung maka akan timbul rasa saling
percaya dan pada akhirnya para anggota
organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang
sudah disepakati Bersama. Hal inilah yang
menjaga konsistensi para anggota untuk terus
melakukan apa yang menjadi tujuan di
bentuknya komunitas Trashbag. Seperti yang
peneliti lihat antusias para anggota begitu
besar mulai dari rapat persiapan, hari
kegiatan, sampai dengan penyusunan laporan
pertanggungjawaban setelah kegiatan
berakhir. Mereka menunjukkan kinerjanya
berupa selalu aktif dan bertanya apakah ada
kekurangan untuk mempersiapkan kegiatan,
mereka juga saling mengingatkan kepada
anggota yang lain ketika ada rapat,
melaksanakan tugas masing-masing dengan
bertanggung jawab, dan ketika ada masalah
yang dihadapi mereka berdiskusi dan mencari
jalan keluarnya.
Pengertian Kinerja menurut beberapa ahli
adalah sebagai berikut: (Veithzal Rivai dan
Ahmad Fawzi, 2005) : (1) Kinerja merupakan
seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk
pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan
sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch
and Keeps, 1992). (2) Kinerja merupakan salah
satu kumpulan total dari kerja yang ada pada
diri pekerja (Griffin, 1987), (3) Kinerja
merupakan suatu fungsi dari motivasi dan
kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau
pekerjaan seseorang harus memiliki derajat
kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah
cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu
tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang
akan dikerjakan dan bagaimana
mengerjakannya (Hersey and Blanchard,
1993), (4) Kinerja merujuk kepada tingkat
keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta
kemampuan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan
sukses jika tujuan yang diinginkan dapat
tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and
Ivancevich, 1994), (5) Kinerja sebagai kualitas
dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik
yang dilakukan oleh individu, kelompok
maupun perusahaan (Schermerhorn, Hunt
and Osborn, 1991), (5) Kinerja sebagai fungsi
interaksi antara kemampuan(Ability =A),
motivasi (motivation=M) dan kesempatan
(opportunity=O) atau Kinerja = ƒ(A x M x O);
artinya: kinerja merupakan fungsi dari
kemampuan, motivasi dan kesempatan
(Robbins,1996).
E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian iklim
komunikasi yang terjadi pada Trashbag Palu,
maka dapat di tarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut. Berdasarkan pada poin
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 79
supportiveness, dapat disimpulkan bahwa
Pater dan Sham selaku ketua Trashbag dan
Ketua Panitia selalu memberi dukungan
dalam hal pengambilan keputusan dan ketika
anggota akan melakukan tugasnya masing-
masing. Berdasarkan pada poin partisipasi,
dapat disimpulkan bahwa semua anggota
Trashbag Palu dan panitia Sapu Jagad
berpartisipasi secara sukarela meskipun motif
mereka untuk bergabung berbeda-beda.
Berdasarkan poin kepercayaan, dapat
disimpulkan bahwa anggota/sukarelawan
Trashbag menaruh rasa percaya berdasarkan
kenyamanan masing-masing. Kenyamanan
yang dimaksud adalah karena bermacam
alasan, salah satunya nyaman karena berada
di lingkungan studi yang sama sehingga
menimbulkan rasa percaya karena sering
bertemu. Berdasarkan poin keterbukaan,
dapat disimpulkan bahwa keterbukaan akan
sangat membantu untuk memenuhi
kebutuhan yang di perlukan oleh anggota
komunitas. Berdasarkan poin tujuan kinerja
yang tinggi, dapat di simpulkan bahwa
Trashbag adalah komunitas yang
memberlakukan sistem fleksibel tidak
mengikat sehingga membuat para anggota
bisa lebih terbuka. Ketika semua anggota
merasa terbuka satu sama lain untuk
mencapai visi dan misi komunitas menurut
peneliti bisa lebih maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar. 1984. Strategi Komunikasi
Sebuah Pengantar Ringkas. Bandung :
ARMICO
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif.
Jakarta : Kencana Predana Media Group
Cangara, Hafied. 2011. Pengantar Ilmu
Komunikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada
Chatia Hastasari. 2007. Menggagas Pencitraan
Berbasis Kearifan Lokal
Curtis, Dan B., Floyd, James J., Winsor, Jerry
L., 2005. Komunikasi Bisnis dan
Profesional. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Effendi, Onong Uchjana. 2013. Ilmu
Komunikasi Teori dan Praktek.
Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Emzir. 2010. Metodologi Penelitian
Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif.
Jakarta : Rajawali Pers
Jalaludin, Rakhmat. 1994. Psikologi
Komunikasi. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis
Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana
Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss, 2009.
Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta :
Salemba Humanika
Mardalis. 2010. Metode Penelitian (suatu
pendekatan proposal). Jakarta : Bumi
Aksara
Miftah, Thoha, 2010. Kepemimpinan dan
Manajemen. Devisi Buku Perguruan
Tinggi. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 80
Moleong, J, Lexy. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Muhammad, Arni, 1995, Komunikasi
Organisasi, Jakarta : Bumi Aksara
Muhammad, Arni. 2003. Ilmu, Teori dan
Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra
Aditya Bakti
Muhammad, Arni. 2004. Komunikasi
Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara
Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. 2000.
Komunikasi Organisasi Strategi
Meningkatkan Kinerja Perusahaan.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Ruslan, Rosady. 2008. Manajemen Public
Relations & Media Komunikasi. Jakarta
: PT. Rajagrafindo Persada
Suryabrata, Sumadi. 2011. Metodologi
Penelitian. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada
Wiryanto, 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi.
Jakarta : PT. Grasindo
Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi.
Yogyakarta : Andi
www.menlhk.go.id di akses tanggal 20 April
2017 Pukul 19:35
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 81
THERAPEUTIC COMMUNICATION OF DOCTORS AND PATIENTS IN THE DISEASE IN ANUTAPURA HOSPITAL
KOMUNIKASI TERAPEUTIK DOKTER DAN PASIEN PADA BAGIAN PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT UMUM ANUTAPURA PALU
RENALDO MARTIN KRISTANTO TORILE 1
1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah E-mail:
Naskah diterima : 9 April 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
This study was conducted aimed at finding out the therapeutic communication (interpersonal) of doctors in
approaching patients on examination activities. The research method used is qualitative research with
descriptive methods. Location is located at Anutapura Palu General Hospital Jl. Kangkung No. 1. The number
of informants in this study were 6 (six) people with accidental sampling withdrawal techniques by
determining the criteria determined by the researcher. Data collection techniques are carried out by
observation and interviews. The data analysis technique uses qualitative data analysis. The results showed that
the doctor's therapeutic communication and internal medicine patients can be seen based on direct
interpersonal communication, namely the first reaction, lack of reaction indicated by the doctor at the
introductory stage or the beginning of the examination. good by giving the right advice for healing patients.
Both relationships, doctors build good relationships by approaching patients and providing fair services to
patients they handle. The third message flow, communication is established where the doctor as the leader and
director in communication so that the patient gets a medical consultation and good understanding.
Keywords : communication, interpersonal, terapeuthic
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui komunikasi terapeutik (interpersonal) dokter dalam
melakukan pendekatan kepada pasien pada kegiatan pemeriksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi bertempat di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu Jl.
Kangkung No. 1. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang dengan teknik penarikan
accidental sampling dengan menentukan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik dokter dan pasien penyakit dalam dapat dilihat
berdasarkan komunikasi interpersonal secara langsung yaitu yang pertama reaksi, kurangnya reaksi yang
ditunjukkan dokter pada tahap perkenalan atau awal pemeriksaan, proses pemeriksaan menunjukan reaksi
yang positif ketika pemeriksaan tengah berlangsung dimana dokter mampu membangun komunikasi yang
baik dengan pemberian saran yang tepat untuk kesembuhan pasien. Kedua hubungan, dokter membina
hubungan yang baik dengan dengan melakukan pendekatan kepada pasien dan memberikan pelayanan yang
adil kepada pasien-pasien yang ditanganinya. Ketiga arus pesan, komunikasi terjalin dimana dokter sebagai
pemimpin dan pengarah dalam komunikasi sehingga pasien mendapat konsultasi pengobatan dan
pemahaman yang baik.
Kata Kunci : komunikasi, interpersonal, terapeutik
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 82
A. PENDAHULUAN
Komunikasi pada dasarnya sangat
diperlukan oleh makhluk hidup. Berhasilnya
segala kegiatan yang dilakukan baik secara
langsung maupun tidak langsung sangat
bergantung pada lancarnya komunikasi yang
dilakukan oleh individu masing-masing.
Tanpa komunikasi segala kegiatan ataupun
pekerjaan tidak akan pernah terlaksana
dengan baik, oleh karena itu baik secara
langsung maupun tidak komunikasi sangat
diperlukan, terutama di zaman sekarang yang
semakin hari semakin maju.
Kegiatan komunikasi yang paling sering
dilakukan adalah komunikasi interpersonal.
Komunikasi interpersonal merupakan
komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang
secara tatap muka, dan saling memberi respon
atau umpan balik terhadap apa yang
disampaikan. Dapat dikatakan komunikasi
interpersonal apabila komunikasi terjadi
antara satu orang pembawa pesan kepada
penerima pesan, bisa satu orang ataupun satu
kelompok kecil dan penerima pesan bisa
menangkap pesan yang diberikan dan segera
memberikan umpan balik atas apa yang
disampaikan oleh pembawa pesan.
Kegiatan komunikasi berperan sangat
penting dalam kehidupan sehari-hari, oleh
karena itu komunikasi bisa juga dijadikan alat
terapi atau suatu metode pada profesi-profesi
tertentu, yang dalam menjalankan tugasnya
sangat sering berhubungan dengan orang lain.
Kegiatan tersebut biasanya berhubungan
dengan profesi psikologi, konseling kesehatan
medis atau kedokteran, dan klinik alternatif,
sehingga komunikasi dapat berfungsi sebagai
alat terapi. Komunkasi dalam bidang
kesehatan sangatlah penting sebab tanpa
komunikasi pelayanan kesehatan sulit
diaplikasikan. Pada pelayanan kesehatan,
komunikasi ditujukan untuk mengubah
perilaku klien guna mencapai tingkat
kesehatan yang optimal. komunikasi dalam
bidang kesehatan disebut komunikasi
terapeutik.
Proses penyembuhan yang dialami pasien
tidak lepas dari peran dokter yang menangani
permasalahan pasien. Metode pengobatan
serta pendekatan komunikasi terapeutik yang
dilakukan oleh dokter sangat menentukan
bagaimana tingkat kesembuhan pasien.
Apabila komunikasi yang dilakukan baik
maka dokter akan lebih mudah mendapatkan
solusi atas apa yang menjadi permasalahan
pasien karena dokter dapat menggali
permasalahan pasien melalui komunikasi dan
dokter dapat mengambil keputusan yang
tepat dalam memberikan solusi untuk
kesembuhan pasien, baik dalam segi
pemberian obat-obatan dan juga saran untuk
membantu penyembuhan. Jika komunikasi
yang dilakukan dokter mengalami hambatan,
dokter sendiri akan mengalami masalah
dalam pengambilan keputusan nantinya.
Rumah Sakit Umum Anutapura Palu,
salah satu rumah sakit yang terletak di pusat
kota dan yang telah lama berdiri di kota Palu
sehingga memiliki pasien yang cukup banyak
setiap harinya, termasuk pasien untuk
penyakit dalam. Berdasarkan data dari rekam
medis RSU Anutapura Palu dalam tiga tahun
terakhir, pada tahun 2015 kunjungan pasien
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 83
untuk penyakit dalam berjumlah 15.749,
kemudian pada tahun 2016 kunjungan pasien
untuk penyakit dalam berjumlah 11.469. Pada
tahun 2017 kunjungan pasien untuk penyakit
dalam sampai pada bulan September sudah
sebanyak 6.676 pasien, sedangkan di tahun
2015 kunjungan pasien sampai bulan
September sebanyak 12.490 pasien, dan di
tahun 2016 kunjungan pasien sampai bulan
September sebanyak 8.615 pasien.
Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan
terhadap jumlah kunjungan pasien pada
bagian penyakit dalam.
Pada observasi awal, peneliti mendapati
pasien dari penyakit dalam di RSU Anutapura
yang menyatakan ketidakpuasan mengenai
pemeriksaannya karena kurang diberikan
informasi tentang penyakit yang diderita oleh
pasien. Pasien ingin diberikan informasi
secara terperinci baik hal-hal apa saja yang
menjadi pantangan untuk dilakukan atau hal-
hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh pasien
agar membantu proses penyembuhannya.
Peneliti juga melakukan pengamatan pada
lokasi spesialis penyakit dalam dimana tempat
antrian pasien cukup padat dan bersebelahan
dengan ruangan spesialis penyakit-penyakit
lainnya, dan didalam ruangan proses
komunikasi hanya terjadi ketika pemeriksaan
antara dokter dan pasiennya.
Kunjungan pasien penyakit dalam
terhitung banyak, oleh karena itu sangat
penting bagi tenaga medis di rumah sakit
dalam melakukan penanganan terhadap
pasiennya, terutama dalam menangani pasien
yang banyak, sehingga keterampilan dokter
baik dalam segi teknik dan pelaksanaan
komunikasi sangat dibutuhkan. Terutama
dalam menangani pasien yang memiliki
penyakit parah seperti penyakit dalam,
komunikasi dokter kepada pasien yang
bersangkutan harus lebih hati-hati agar
membuat pasien tidak trauma, serta pasien
dapat memperoleh pengetahuan dalam
mengatasi segala permasalahan mengenai
kesehatan bagi dirinya sendiri.
Peneliti menentukan judul berdasarkan
latar belakang diatas, karena ingin mengetahui
bagaimana komunikasi interpersonal yang
dilakukan dokter sebagai salah satu metode
terapi guna membantu kesembuhan pasien,
secara khusus pasien penyakit dalam.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat
judul penelitian tentang Komunikasi
Terapeutik Dokter dan Pasien Pada Bagian
Penyakit Dalam Di Rumah Sakit Umum
Anutapura Palu.
B. Komunikasi Interpersonal
Komunikasi dalam psikologi mempunyai
makna yang luas, meliputi segala
penyampaian energi, gelombang suara, tanda
diantara tempat, sistem atau organisme. Kata
komunikasi sendiri dipergunakan sebagai
proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau
secara khusus sebagai pesan pasien dala
psikoterapi. Psikologi menyebut komunikasi
pada penyampaian energi dari alat-alat indera
ke otak, pada peristiwa penerimaan dan
pengolahan informasi, pada proses saling
pengaruh diantara berbagai sistem dalam diri
organisme dan diantara organisme.
Psikologi juga tertarik pada pada
komunikasi di antara individu (komunikasi
interpersonal) : bagaimana pesan dari seorang
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 84
individu menjadi stimulus yang menimbulkan
respon pada individu yang lain. Pada saat
pesan sampai kepada komunikator, psikologi
melihat ke dalam proses penerimaan pesan,
menganalisa faktor-faktor personal dan
situasional yang mempengaruhinya, dan
menjelaskan bebagai corak komunikan ketika
sendiri atau dalam kelompok (Rakhmat
2011:5).
Komunikasi interpersonal, disebut juga
komunikasi antarpribadi, inter artinya antara,
personal berarti pribadi. Komunikasi
interpersonal adalah komunikasi antar orang-
orang secara tatap muka, yang
memungkinkan setiap peserta menangkap
reaksi yang lain secara langsung, baik secara
verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang
efektif ditandai dengan hubungan
interpersonal yang baik. Setiap kali kita
melakukan komunikasi, kita bukan hanya
sekedar menyampaikan isi pesan; kita jugan
menentukan kadar hubungan interpersonal,
bukan hanya menentukan "content" tetapi juga
"relationship" (Makarao 2010:66). Komunikasi
yang dilakukan secara verbal dilakukan secara
lisan maupun dengan cara tertulis, sedangkan
nonverbal dilakukan dengan menggunakan
gerakan atau bahasa isyarat.
DeVito (Suranto 2011:4), menjelaskan
bahwa komunikasi interpersonal adalah
penyampaian pesan oleh satu orang dan
penerimaan pesan oleh orang lain atau
sekelompok kecil orang, dengan berbagai
dampaknya dan dengan peluang untuk
memberikan umpan balik segera. Komunikasi
ini juga terjadi diantara kelompok kecil orang,
dibedakan dari publik atau komunikasi massa;
komunikasi sifat pribadi, dibedakan dari
komunikasi yang bersifat umum; komunikasi
diantara orang-orang terhubung atau mereka
yang terlibat dalam hubungan yang erat
(DeVito 2007:334).
John Stewart dan Gary D'Angelo (1980)
(Harapan dan Ahmad 2014:4) memandang
komunikasi berpusat pada kualitas
komunikasi yang terjalin masing-masing
pribadi. Partisipan berhubungan satu sama
lain sebagai seorang pribadi yang memiliki
keunikan, mampu memilih, berperasaan,
bermanfaat, dan merefleksikan dirinya sendiri
daripada sebagai objek atau benda. Dalam
berkomunikasi, seseorang dapat bertindak
atau memilih peran sebagai komunikator
maupun sebagai komunikan.
Gerald R. Miller (1976) (Rakhmat
2011:118), menulis kata pengantar untuk buku
Explorations in interpersonal Communication
menyatakan bahwa :
"Memahami proses komunikasi
interpersonal menuntut pemahaman
hubungan simbiotis antara
komunikasi dengan perkembangan
relasional: Komunikasi
mempengaruhi perkembangan
relasional, dan pada gilirannya (secara
serentak), perkembangan relasionall
mempengaruhi sifat komunikasi
antara pihak-pihak yang terlibat
dalam hubungan tersebut."
Bungin (2008:32) juga menjelaskan tentang
komunikasi interpersonal bahwa :
"Komunikasi interpersonal adalah
komunikasi antar-perorangan yang
bersifat pribadi baik yang terjadi
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 85
secara langsung maupun tidak
langsung. Contohnya kegiatan
percakapan tatap muka, percakapan
melalui telepon, surat menyurat
pribadi. Fokus pengamatannya adalah
bentuk-bentuk dan sifat hubungan
(relationship), percakapan (discourse),
interaksi dan karakteristik
komunikator".
Dengan demikian, komunikasi
interpersonal akan mencakup seperti
komunikasi antara anak dengan ayahnya,
majikan dengan karyawan, kakak beradik,
guru dengan murid, orang berpacaran, dua
teman dan sebagainya. Komunikasi
interpersonal merupakan komunikasi yang
frekuensi terjadinya cukup tinggi dalam
kehidupan sehari-hari.
DeVito (2011:285-291) menjelaskan bahwa
dalam pendekatan humanistis dalam
komunikasi interpersonal memiliki lima
efektivitas yang diperlukan, yaitu:
keterbukaan (openess), empati (empathy),
sikap mendukung (supportiveness), sikap
positif (positiveness), dan kesetaraan
(equality).
1. Keterbukaan (Openness)
Kualitas keterbukaan mengacu pada
sedikitnya tiga aspek dari komunikasi
interpersonal. Pertama, komunikator
interpersonal yang efektif harus
terbuka kepada orang yang diajaknya
berinteraksi. Aspek kedua mengacu
pada kesediaan komunikator untuk
bereaksi secara jujur terhadap
stimulus yang datang. Aspek ketiga
menyangkut "kepemilikan" perasaan
dan pikiran (Bochner dan kelly, 1974).
2. Empati (Empathy)
Berempati adalah merasakan sesuatu
seperti orang yang mengalaminya,
berada dikapal yang sama dan
merasakan perasaan yang sama
dengan cara yang sama. Orang yang
empati mampu memahami motivasi
dan pengalaman orang lain, perasaan
dan sikap mereka, serta harapan dan
keinginan mereka untuk masa
mendatang.
3. Sikap Mendukung (Suportiveness)
Hubungan antarpribadi yang efektif
adalah hubungan dimana terdapat
sikap mendukung. Komunikasi yang
terbuka dan empatik tidak dapat
berlangsung dalam suasana yang
tidak mendukung.
4. Sikap Positif (Positiveness)
Sikap positif mengacu pada sedikitnya
dua aspek dari komunikasi
antarpribadi. Pertama komunikasi
antarpribadi akan terbina jika orang
memiliki sikap positif terhadap diri
mereka sendiri. orang yang merasa
negatif terhadap diri sendiri selalu
mengkomunikasikan perasaan ini
kepada orang lain, yang selanjutnya
barangkali akan mengembangkan
perasaan negatif yang sama.
Sebaliknya, orang yang merasa positif
dengan diri sendiri mengisyaratkan
perasaan ini kepada orang lain, yang
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 86
selanjutnya juga akan merefleksikan
perasaan positif ini.
5. Kesetaraan (Equality)
Dalam suatu hubungan antarpribadi
yang ditandai oleh kesetaraan,
ketidaksependapatan dan konflik
lebih dilihat sebagai upaya untuk
memahami perbedaan yang pasti ada
daripada sebagai kesempatan untuk
menjatuhkan pihak lain.
Komunikasi interpersonal merupakan
jenis komunikasi yang paling efektif karena
melakukan adanya tatap muka sehingga
menyebabkan tingkat emosi dan keakraban
yang lebih baik dan nyata, dan hal ini yang
membedakan jenis komunikasi interpersonal
dengan jenis komunikasi massa melalui media
cetak atau elektronik. Komunikasi
interpersonal dapat terjadi secara langsung
(tatap muka) atau tidak secara langsung
melalui perantara media. Adanya perantara
ini yaitu memberikan pengaruh yang lebih
luas mengenai informasi yang diberikan,
dapat melalui media cetak, media elektronik
ataupun online.
C. Komunikasi Terapeutik
Komunikasi interpersonal yang terjadi
cenderung tertutup atau bersifat pribadi
karena komunikasi yang dilakukan hanya
antara pengirim dan penerima pesan, atau
orang-orang dalam kelompok kecil. Oleh
karena itu untuk melakukan pendekatan
kepada pasien dalam melakukan
penyembuhan, ahli-ahli kesehatan
menggunakan metode lain dari komunikasi
interpersonal, yaitu komunikasi terapeutik.
Komunikasi terapeutik merupakan metode
yang dipakai untuk membantu ahli-hli
kesehatan, dokter maupun perawat.
Komunikasi terapeutik tergolong komunikasi
interpersonal dengan titik landasan dasar
saling memberi pengertian antara tenaga
kesehatan dengan pasien/klien (Lalongkoe
dan Edison 2014:117).
D. Metodologi Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
berarti proses eksplorasi dan memahami
makna perilaku individu dan kelompok,
menggambarkan masalah sosial atau masalah
kemanusiaan. Hal ini bertujuan
menggambarkan realitas yang sedang terjadi
dengan membuat deskripsi secara sistematis,
faktual dan akurat yang menggambarkan
kejadian yang terjadi dilapangan (Kriyantono
2007:69).
Dasar penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ilmu komunikasi pada
konteks komunikasi interpersonal, dengan
metode deskriptif. Metode deskriptif berarti
penelitian yang berusaha mendeskripsi dan
mengiterpretasi kondisi atau hubungan yang
ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses
yang sedang berlangsung, akibat yang sedang
terjadi atau kecenderungan yang tengah
berkembang (Sumanto 1990:47). Penggunaan
metode deskriptif untuk mengumpulkan
suatu kenyataan yang ada atau yang terjadi
dilapangan agar dapat dipahami secara
mendalam, dan akhirnya diperoleh temuan
data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian
terkait dengan komunikasi terapeutik
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 87
(interpersonal) dokter dan pasien pada bagian
penyakit dalam di RSU Anutapura Palu.
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah
Sakit Umum Anutapura, Jl. Kangkung No. 1
Palu, Sulawesi Tengah. Objek penelitian yaitu
apa yang menjadi sasaran penelitian secara
konkret tergambarkan dalam rumusan
masalah penelitian, yaitu bagaimana
komunikasi dalam komunikasi interpersonal
dokter dan pasien secara langsung dalam
melakukan pendekatan kepada pasien
penyakit dalam di RSU Anutapura. Dalam
pencarian sampel untuk subjek penelitian
menggunakan teknik nonprobability
sampling, dengan metode accidental
sampling. Accidental sampling adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan,
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu
dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data
(Sugiyono, 2014: 156). Kriteria sebagai
prasyarat dalam penentuan informan yaitu
pasien yang sering berkunjung ke bagian
penyakit dalam, usia informan minimal 28
tahun keatas mengingat diusia tersebut sudah
rentan terkena penyakit, mampu memberikan
informasi yang jelas, serta merupakan pasien
yang diperiksa oleh dokter yang menjadi
sumber dalam penelitian.
Reduksi data dilakukan ketika data telah
dikumpulkan. Reduksi data dilakukan dengan
cara menganalisis hasil wawancara,
merangkum, memilih dan memfokuskan
kepada hal yang penting yang diperlukan
dalam penelitian terutama dalam
pengumpulan data. Terkait bagaimana data
yang diperoleh dapat dikaitkan dengan teori-
teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya hasil reduksi disajikan dalam
bentuk skrip wawancara. Penyajian tersebut
kembali direduksi, dengan memilah-milah
data yang penting serta menentukan data
yang masih kurang lengkap sehingga dapat
ditarik kesimpulan-kesimpulan sehubungan
dengan penelitian. Untuk data yang masih
kurang lengkap, maka peneliti kembali
melakukan pengumpulan data, dilanjutkan
dengan reduksi penyajian dan penarikan
kesimpulan.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan ini bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai
bagaimana komunikasi interpersonal dokter
dalam kunjungan pasien di bagian pennyakit
dalam. Keberhasilan dalam proses
pemeriksaan juga tergantung dari
kemampuan dokter sendiri dalam melakukan
komunikasi yang baik dengan semua pasien
yang ditangani. Peneliti telah memperoleh
gambaran tentang komunikasi terapeutik
(interpersonal) dokter dan pasien pada bagian
penyakit dalam di RSU Anutapura Palu.
Komunikasi interpersonal juga dipakai
para ahli-ahli kesehatan dalam membantu
kesembuhan klien yang dihadapinya. Tenaga
kesehatan dalam hal ini dokter, selain
memberikan obat-obatan terkait kesembuhan
pasien juga diharuskan melakukan interaksi
dengan pasien agar mendapatkan informasi
yang lebih dan bisa membaca situasi yang
terjadi pada saat proses pemeriksaan di dalam
ruangan, sehingga dokter mendapatkan
informasi tambahan serta memberi informasi
tambahan mengenai permasalahan yang
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 88
dihadapi pasiennya. Salah satu hal yang
biasanya dokter lupakan pada saat
pemeriksaan yaitu membangun interaksi
terhadap pasiennya sendiri, sehingga kadang
dokter kebanyakan keliru dalam pemberian
obat-obatan dan kurang dalam pemberian
saran-saran dan akhirnya pasien menjadi tidak
puas dengan pemeriksaannya. Oleh karena itu
komunikasi dalam tenaga kesehatan sangat
penting.
Untuk mengetahui bagaimana komunikasi
interpersonal dokter yang terjadi, maka
dipakai komunikasi interpersonal secara
langsung untuk menggali informasi dari
pasien pada saat pemeriksaannya.
Komunikasi terapeutik tergolong komunikasi
interpersonal dengan titik landasan dasar
saling memberi pengertian antara tenaga
kesehatan dengan pasien/klien (Lalongkoe
dan Edison 2014:117). DeVito (Suranto 2011:4)
menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal
adalah penyampaian pesan oleh satu orang
dan penerimaan pesan oleh orang lain atau
sekelompok kecil orang, dengan berbagai
dampaknya dan dengan peluang untuk
memberikan umpan balik segera. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, peneliti
mendapatkan gambaran komunikasi
terapeutik dokter terhadap pasien bagian
penyakit dalam melalui komunikasi
interpersonal secara langsung dengan
memperhatikan pada reaksi, hubungan, dan
arus pesan.
Komunikasi yang diberikan pengirim
pesan akan menimbulkan reaksi kepada
penerima pesan, sehingga dapat membangun
sikap empati. Empati ada ketika terjadi
hubungan yang baik dan saling percaya antara
satu dengan yang lainnya, dan sebagai
kemampuan seseorang untuk mengetahui apa
yang sedang dialami orang lain pada suatu
saat tertentu, dari sudut pandang orang itu,
dan melalui kacamata orang itu. Dengan
empati kita mampu merasakan kondisi
emosional orang lain, sehingga bisa
menciptakan suatu hubungan dengan baik
dengan orang lain.
Orang yang memiliki rasa empati akan
mampu memahami motivasi dan pengalaman
orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta
harapan dan keinginan mereka untuk masa
mendatang. Sikap ini sangat dokter butuhkan
dalam melakukan pemeriksaan di rumah
sakit, dengan empati akan membuat dokter
bisa terbiasa melihat sesuatu dari sisi yang
lain. Dengan pendekatan emosional pasien
akan menunjukkan reaksi dan membantu
dokter dalam memisahkan masalah yang
dialami pasien dengan hal yang tidak perlu
dibahas, dan akan mendorong dokter untuk
lebih melihat bagaimana menyelesaikan
masalah yang dialami pasien dengan baik.
Dokter bagian penyakit dalam RSU
Anutapura telah memberikan reaksi yang
positif dalam proses pemeriksaan, dengan
menunjukkan sikap dan reaksi yang peka
dengan situasi dokter mampu membangun
komunikasi dan pasien tidak ragu dalam
mengemukakan permasalahannya sehingga
dokter bisa memberi saran-saran terbaik demi
kesembuhan pasien, sesuai dengan yang
disampaikan DeVito (2011) bahwa orang yang
empati mampu memahami motivasi dan
pengalaman orang lain, perasaan dan sikap
mereka, serta harapan dan keinginan mereka
untuk masa mendatang. Berarti dokter
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 89
mampu menganalisa situasi sehingga dokter
dapat membangun komunikasi yang baik.
Dokter berbagi kepada pasien mengenai
pengalamannya atau pengalaman pasien lain
yang memiliki permasalahan yang serupa
yang dialami oleh pasien saat melakukan
pemeriksaan, meskipun tidak terlalu detail
karena keterbatasan waktu, namun bisa
membantu dalam melakukan pemeriksaan.
Namun untuk terjalinnya komunikasi yang
baik dalam memberikan penjelasan mengenai
permasalahan pasien, perlu keterlibatan dari
pasien itu sendiri. Apabila pasien bersikap
pasif dalam komunikasi maka proses
pemeriksaan akan berjalan datar.
Selanjutnya, komunikasi yang efektif
apabila adanya sikap saling mendukung
antara satu sama lain. Artinya masing-masing
dari dari pihak yang melakukan komunikasi
memiliki komitmen untuk saling mendukung
terselenggaranya komunikasi secara terbuka.
Dukungan merupakan pemberian dorongan
atau pengobaran semangat kepada orang lain
dalam suasana hubungan komunikasi.
Sehingga dengan adanya dukungan dalam
situasi apapun, komunikasi interpersonal akan
bertahan lama karena tercipta suasana yang
mendukung.
Dokter di bagian penyakit dalam di RSU
Anutapura menunjukkan sikap positif dalam
mendukung pasien yang dia tangani, melalui
saran-saran dan pantangan-pantangan yang
diberitahukan dokter sesuai dengan
permasalahan dari masing-masing pasien. Hal
ini cocok dengan pernyataan Northouse
(Suryani 2006) yang menyatakan komunikasi
terapeutik merupakan kemampuan atau
keterampilan perawat untuk membantu klien
beradaptasi terhadap stres mengatasi
gangguan psikologis dan belajar bagaimana
berhubungan dengan orang lain. Dengan
pemberian saran-saran yang tepat kepada
pasien dan apa-apa saja yang menjadi
pantangan pasien, serta dengan pemberian
obat yang tepat maka dokter sudah bersikap
mendukung pasiennya.
Namun yang menjadi kendala dari
penanganan di ruangan adalah kesan pertama
atau perkenalan pada saat bertemu dengan
dokter dikarenakan dokter yang terkesan cuek
dan ketika berada diruangan juga meskipun
ramai pasien tapi suasananya hening sehingga
pasien merasa gugup pada awal pemeriksaan.
Oleh karena itu sikap mendukung yang
ditunjukan dokter itu muncul ketika
melakukan komunikasi dan direspon baik
oleh pasien itu sendiri dengan memberikan
reaksi baik atas apa yang disampaikan oleh
dokter. Sikap yang mendukung dari dokter
baik dari kesan awal pemeriksaan dan
pemeriksaan lebih lanjut sangat dibutuhkan
pasien agar pasien mendapatkan perhatian
lebih serta mendapatkan solusi penyembuhan
yang baik agar sesuai seperti yang dikatakan
DeVito (2011) yang menyatakan komunikasi
yang terbuka dan empati tidak dapat
berlangsung dalam suasana yang tidak
mendukung.
Selanjutnya, sikap positif dalam
membangun hubungan komunikasi dapat
ditunjukan dalam bentuk sikap dan perilaku,
dalam bentuk sikap berarti orang-orang yang
terlibat komunikasi harus mempunyai pikiran
dan perasaan positif tanpa harus saling
menaruh curiga satu sama lain, dan bentuk
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 90
perilaku berarti tindakan yang dilakukan
berdasarkan komunikasi interpersonal yaitu
melakukan aktivitas untuk menjalin
kerjasama. Dengan bersikap positif maka kita
dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan
sikap-sikap yang baik yang dapat membuat
orang menjadi bersemangat, melakukan hal-
hal yang benar dan menjadi bahagia. Oleh
karena itu dengan membangun hubungan
dalam sebuah pembicaraan kita akan
mendapatkan kesan yang positif, terutama
untuk proses pemeriksaan yang dilakukan di
rumah sakit agar baik itu dokter dan pasien
dapat menjalin hubungan melalui komunikasi
yang baik sehingga terjalin kerjasama dalam
mengatasi permasalahan oleh pasien.
Dokter di bagian penyakit dalam RSU
Anutapura pada awal pemeriksaan terkesan
cuek, sikap positif ditunjukkan ketika proses
komunikasi berlangsung sehingga pasien
yang ditangani dalam melakukan
pemeriksaan merasa nyaman di dalam
ruangan tersebut agar sesuai dengan yang
dikatakan DeVito (2011) bahwa komunikasi
antarpribadi akan terbina jika orang memiliki
sikap positif terhadap diri mereka sendiri.
Dokter dalam berkomunikasinya yang baik
dan santai sehingga membangun komunikasi
yang baik kepada pasien. Purwanto (1994:25)
menyatakan salah satu manfaat dari
komunikasi terapeutik yaitu Mendorong dan
menganjurkan kerjasama antara perawat
dengan klien melalui hubungan perawat
dengan klien, oleh karena itu dokter perlu
memperhatikan dalam melihat kondisi atau
peluang yang tepat dalam membangun
komunikasi, dan membuat pasien yang
ditanganinya juga ikut berpikiran positif, lebih
terbuka dalam menyampaikan
permasalahannya.
Kesetaraan dalam membangun hubungan
merupakan pengakuan bahwa kedua pihak
sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa
masing-masing pihak saling memerlukan satu
sama lain. Secara alamiah ketika dua orang
berkomunikasi secara interpersonal, tidak
pernah mencapai situasi yang menunjukkan
kesetaraan atau kesamaan secara utuh
diantara keduanya. Pasti ada yang lebih kaya,
lebih pintar, lebih muda, atau pun lebih
berpengalaman dalam bidangnya masing-
masing. Namun kesetaraan yang
dimaksudkan disini adalah berupa pengakuan
atau kesadaraan seseorang dan juga kerelaan
untuk menempatkan diri setara dengan siapa
saja yang diajak berkomunikasi.
Dokter di bagian penyakit dalam di RSU
Anutapura bersikap adil ketika melakukan
pemeriksaan, maka pasien yang berada di
ruangan pemeriksaan tidak tegang karena
pasien melihat dokter memberikan pelayanan
yang baik dengan pasien-pasien sebelumnya.
Dokter dalam melakukan pemeriksaan
menjelaskan dengan kata-kata yang mudah
dipahami, dengan lebih menyederhanakan
bahasanya agar dapat di mengerti pasien dari
berbagai golongan.
Dengan bersikap setara dengan orang lain
maka pelayanan yang dilakukan dokter dapat
terlaksana dengan baik karena dengan
menunjukkan kesetaraan maka pasien tidak
lagi membatasi dirinya dan tidak ragu dalam
berkomunikasi dengan dokter, sehingga
permasalahan yang dialami pasien dapat
menemukan solusi yang tepat dan tidak
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 91
terjadi salah paham yang tidak perlu diantara
keduanya ketika pemeriksaan berlangsung,
agar sesuai dengan yang dikatakan DeVito
(2011) yang menyatakan bahwa dalam suatu
hubungan antarpribadi yang ditandai oleh
kesetaraan, ketidaksependapatan dan konflik
lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami
perbedaan yang pasti ada daripada sebagai
kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain.
Dengan adanya kesetaraan dalam melakukan
komunikasi maka segala hal yang dibahas
dalam pembicaraan baik itu antara kedua
belah pihak dapat saling mengerti dan
permasalahan yang ada dalam pembicaraan.
Komunikasi yang dilakukan secara
langsung sangat diperlukan apabila kita ingin
mengetahui arus pesan dan umpan balik dari
orang yang kita ajak berkomunikasi.
Aguserele (Makarao 2010:75) menyatakan
pemberian sentuhan kepada pasien
membuktikan peningkatan komunikasi verbal
dan mendorong pasien untuk mengadakan
pendekatan kepada orang lain secara lebih
sering. Maka dalam melakukan pemeriksaan
kesehatan pun sangat efektif apabila
dilakukan secara langsung, karena diperlukan
pemeriksaan secara langsung demi
mendapatkan hasil yang baik bagi pasien
pada saat melakukan pemeriksaan bersama
dokter di ruangan pemeriksaan.
Dokter di bagian penyakit dalam di RSU
Anutapura bersikap baik pada saat proses
pemeriksaan dengan mendengarkan keluhan
pasien kemudian memberikan informasi yang
cukup bagi pasien yang ditangani, pada saat
pemeriksaan ditempat tidur dokter
melakukan komunikasi dengan pasien untuk
menambahkan informasi mengenai penyakit
pasien. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan
DeVito (Suranto 2011:4) yang menjelaskan
bahwa komunikasi interpersonal adalah
penyampaian pesan oleh satu orang dan
penerimaan pesan oleh orang lain atau
sekelompok kecil orang, dengan berbagai
dampaknya dan dengan peluang untuk
memberikan umpan balik segera. Namun
ketika melakukan pemeriksaan di awal
komunikasi yang terjalin kurang lancar
dikarenakan dokter terkesan cuek.
Komunikasi lancar ketika dalam proses
pemeriksaan, dimana ketika pasien telah
memberitahu permasalahannya kepada dokter
dan dokter melakukan pemeriksaan sehingga
dokter memberikan informasi yang cukup
terkait apa yang perlu diketahui pasien. Pada
saat pemeriksaan dokter bersedia menanggapi
apabila ada hal yang ingin pasien tanyakan.
Keterbukaan merupakan suatu cara untuk
menyingkap perasaan seseorang, dimana
komunikasi yang dilakukan komunikator
dapat dipahami dengan baik oleh komunikan
(penerima pesan). Dalam realita yang ada
dokter akan kesulitan memberikan informasi
apabila pasien tidak mengutarakan dengan
jelas mengenai apa yang menjadi
permasalahannya. Begitu pun dengan pasien,
dokter tidak bisa membaca pikiran pasien
begitu saja apabila komunikasi tidak berjalan
sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu hal
ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan
kegiatan komunikasi interpersonal.
Dokter di bagian penyakit dalam RSU
Anutapura bersikap terbuka terhadap pasien
yang ditanganinya, dengan mempersilahkan
pasien untuk mengutarakan permasalahannya
dan kemudian direspon lebih lanjut oleh
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 92
dokter dengan menjelaskan dengan detail
sehingga komunikasi yang dilakukan berjalan
seimbang, dan pasien yang ditangani bisa
mendapat pengobatan dan pemahaman yang
baik. Dengan sikap dokter yang terbuka,
pasien merasa nyaman dan bisa terbuka juga
kepada dokter yang menanganinya.
Untuk melakukan pemeriksaan yang
efektif, peran keduanya baik dokter dan
pasien harus seimbang, karena akan sangat
sulit apabila pasien yang ditangani bersikap
pasif dalam pemeriksaan, dan ini sesuai
dengan pernyataan dari Bochner dan kelly
dalam DeVito (2011:285-291) yang
menyatakan Kualitas keterbukaan mengacu
pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi
interpersonal. Pertama, komunikator
interpersonal yang efektif harus terbuka
kepada orang yang diajak berinteraksi. Aspek
kedua mengacu pada kesediaan komunikator
untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus
yang datang. Aspek ketiga menyangkut
"kepemilikan" perasaan dan pikiran. Berarti
disini keseimbangan antara dokter dan pasien
dalam berinteraksi menentukan keberhasilann
dalam komunikasi.
F. KESIMPULAN
Dokter Kurang menunjukkan reaksi atau
respon pada tahap perkenalan atau awal
pemeriksaan. Proses pemeriksaan
menunjukan reaksi yang positif ketika
pemeriksaan tengah berlangsung dimana
dokter mampu membangun komunikasi yang
baik dengan pemberian saran yang tepat
untuk kesembuhan pasien. Dokter membina
hubungan yang baik dengan dengan
melakukan pendekatan kepada pasien dan
memberikan pelayanan yang adil kepada
pasien-pasien yang ditanganinya. Komunikasi
terjalin dimana dokter sebagai pemimpin dan
pengarah komunikasi sehingga pasien
mendapat konsultasi pengobatan dan
pemahaman yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
"Palu Tertinggi Kedua Penderita Jantung se
Sulteng". Metrosulawesi. Diakses pada
6 November 2017 <
http://www.metrosulawesi.com/articl
e/palu- tertinggi-kedua-penderita-
jantung-se-sulteng
"Penyakit Jantung di Indonesia Dalam
Angka". Tanyadok. Diakses pada 6
November 2017 <
https://www.tanyadok.com/artikel-
kesehatan/penyakit- jantung-di-
indonesia-dalam-angka
Agus, Salim 2006. Teori & Paradigma
Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara
Wacana
Aw, Suranto. 2011. Komunikasi Interpersonal.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Bungin, Burhan. 2008. Sosiologi Komunikasi
(Teori, Paradigma, dan Discourse
Teknologi Komunikasi di Masyarakat).
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Cangara, Hafied. 2013. Perencanaan dan
strategi komunikasi. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 93
DeVito, Joseph A. 2007. The Interpersonal
CommunicationBook, 11th ed. Boston:
Pearson Education, Inc
DeVito, Joseph A. 2011. Komunikasi
antarmanusia. Tangerang: KARISMA
Publishing Group
Effendy, Onong. 2006. Ilmu Komunikasi; Teori
Dan Praktek. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Fajar, Marhaeni. 2009. Ilmu Komunikasi Teori
& Praktek Edisi Pertama. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis
Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana
Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis:
Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana
Lalongkoe, Maksimus R., dan Edison, Thomas
A. 2014. Komunikasi Terapeutik
Pendekatan Praktisi Dan Kesehatan.
Yogyakarta: Graha Ilmu
Makarao, Nurul Ramadhani. 2010. Neuro
Linguistic Programming; Komunikasi
Konseling; Aplikasi Dalam Pelayanan
Kesehatan. Bandung: Alfabeta
Mas'uda, Emma Fitrotul. 2014. "Hubungan
Komunikasi Terapeutik Perawat
Dengan Kepuasan Pasien Di Unit
Rawat Inap Rumah Sakit Umum (RSU)
Anutapura Palu. Palu: Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Tadulako
Moleong. 1998. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: CV. Remaja
Rosdakarya
Muhammad, Arni. 2009. Komunikasi
Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara
Nasution. 2001, Metode Penelitian Naturalistik
Kualitatif, Bandung: Tarsito.
Rakhmat, Jalaluddin. 2011. Psikologi
Komunikasi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Rekam Medis. Rumah Sakit Umum
Anutapura Palu. Pada 23 Desember
2017. "Penyakit Jantung di
Indonesia Dalam Angka". Tanyadok.
Diakses pada 6 November 2017
< https://www.tanyadok.com/artikel-
kesehatan/penyakit- jantung-di-
indonesia-dalam-angka
Rekam Medis. Rumah Sakit Umum
Anutapura Palu. Pada 23 Desember
2017.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif
kualitatif R&D. Bandung :
Alfabeta
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Manajemen, Bandung: Alfabeta.
Sumanto. 1990. Metodologi Penelitian Sosial
dan Pendidikan. Yogyakarta: Andi
Offset.
Suryani, 2006. Komunikasi Terapeutik Teori
Dan Praktik. Buku Kedokteran. Jakarta :
EGC
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 94
Widjaja. 2000. Ilmu Komunikasi “Pengantar
Studi”. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Windasari, Yuditha Apriliana. 2015.
Hubungan Komunikasi Dokter Dengan
Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Umum (RSU)
Anutapura Palu. Palu: Fakultas
Ilmu Kedoteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Tadulako
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 95
SELF-CONCEPT OF CAREER WOMEN IN FAMILY (Case Study of Working Full-time Housewives in Palu City)
KONSEP DIRI WANITA KARIR DALAM KELUARGA (Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga yang Bekerja Penuh di Kota Palu)
SITI MUNIPA KARIONO1
1Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah E-mail:
Naskah diterima : 4 Juni 2018 Naskah diterbitkan: 29 Juni 2018
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the self-concept of career women and career women's activities in
Palu City. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews and documentation.
Informants in this study were 5 (five) housewives who also worked professionally and researched in Palu City.
The results showed that the career concept of female career was seen in 3 (three) concepts of George Herbert
Mead, namely mind, self, and society. Mind career women are formed from thoughts about the ideal concept
of career women, they consider the ideal career woman is the synergy between career and the main task of
being a mother and wife and from what they experience that being a career woman is not a mistake as long as
she understands her goal for a career and can position himself when becoming a housewife and when working
professionally. Then self is formed because the family background is also a career so that the impulse appears
to be a career woman, besides that because of the encouragement of herself who likes to work and society is
that the closest environment that is family is fully supportive and motivated, the social environment looking
negative does not really affect the decisions of career women in carrying out their dual roles.
Keywords : self-concept, activity, family
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep diri wanita karir dan aktivitas wanita karir di Kota Palu.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) ibu rumah tangga yang juga bekerja secara profesional dan
tempat penelitian di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri wanita karir dilihat dalam 3
(tiga) konsep George Herbert Mead yakni mind, self, dan society. Mind wanita karir dibentuk dari pikiran
mengenai konsep wanita karir yang ideal, mereka menganggap wanita karir yang ideal ialah adanya sinergitas
antara karir dan tugas utama yakni sebagai ibu dan istri dan dari apa yang mereka alami bahwa menjadi
wanita karir bukanlah kesalahan selama paham tujuannya untuk berkarir dan bisa memposisikan dirinya
ketika menjadi ibu rumah tangga dan ketika bekerja secara profesional. Kemudian self terbentuk karena latar
belakang keluarga yang juga berkarir sehingga muncul dorongan untuk menjadi wanita karir, selain itu juga
karena adanya dorongan dari dirinya sendiri yang senang bekerja dan society ialah bahwa lingkungan
terdekat yakni keluarga sangat mendukung penuh dan dijadikan sebagai motivasi, adapun lingkungan sosial
yang memandang negatif tidak begitu berpengaruh pada keputusan wanita karir dalam menjalani peran
gandanya.
Kata Kunci : konsep diri, aktivitas, keluarga
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 96
A. PENDAHULUAN
Konsep wanita karir di Indonesia hari ini
bukan lagi menjadi hal tabu dan sudah
menjadi hal yang wajar dimasyarakat
sekarang ini. Tentunya tidak terlepas dari
dukungan sistem demokrasi dan persamaan
hak asasi manusia. Namun begitu, konsep
wanita karir selalu saja mendapatkan
rintangan, tidak dapat dipungkiri masih
banyak masyarakat di Indonesia terutama di
wilayah-wilayah pedesaan bahkan juga di
wilayah perkotaan masih menganggap wanita
tidak perlu berpendidikan tinggi dan memilki
pekerjaan di bidang profesioanal dan atau
berkarir.
Kota Palu yang merupakan Ibu Kota
Provinsi Sulawesi Tengah, konsep wanita
karir mendapatkan rintangan yang tidak
terhitung mudah. Mulai dari pandangan
keluarga, budaya patriarki, hingga warisan
pemikiran mengenai wanita adalah sosok
yang lemah. Pada akhirnya, pendidikan yang
ditempuh sekian tahun di universitas menjadi
tumpul karena gesekan konflik pemikiran ini.
Tetapi, beberapa wanita di kota ini juga
mampu memperlihatkan potensinya bahkan
menjadi pioneer di bidangnya. Hal ini
membuktikan bahwa wanita dapat
memaksimalkan potensi dan kemampuannya
bahkan melebihi pria yang ada di
lingkungannya. Asumsi pemikiran inilah yang
kemudian dilihat sebagai fokus pada
penelitian ini.
Dalam perspektif komunikasi, wanita-
wanita karir yang hari ini berani mendobrak
kemapanan patriarki memiliki pekerjaan
rumah yang besar terutama pandangan-
pandangan yang memposisikan wanita (ibu)
dalam posisi “Tersangka” utama apabila
seorang anak tidak terurus dengan baik
karena sang ibu sibuk bekerja.
Kontradiksi pandangan tradisional
masyarakat dengan pemikiran pembaharu
menjadikan wanita yang berkarir berada
dalam posisi dilematis. Terutama bagi wanita
yang berkarir bukan semata-mata hanya
persoalan ekonomi, melainkan motif psikologi
sebagai workaholic atau perempuan yang
berkakarir karena mengikuti lingkungan
sosialnya. Di Kota Palu, sebagai Ibu Kota
Provinsi yang terus berkembang, wanita
memiliki peranan penting dalam
pembangunan kota. Wanita yang berkakrir
sebagai workaholic secara tidak sadar juga
ikut memberikan sumbangsih bagi
masyarakat. Motif psikologi yang berdampak
sosial.
Dalam perspektif komunikasi, perbedaan
motif berperilaku dapat dilihat melalui
interkasionisme simbolik. Kajian
Interaksionisme Simbolik, wanita karir sebagai
pelaku komunikasi berperilaku berdasarkan
interaksi dengan lingkungannya oleh Goerge
Herbert Mead, disebut sebagai konsep diri.
Dua asumsi konsep diri yang penting dalam
penelitian ini dan digunakan untuk
memahami fenomena perilaku dan motif
wanita karir adalah bahwa individu
mengembangkan konsep diri melalui interaksi
dengan orang lain dan konsep diri
memberikan motif yang penting untuk
berperilaku.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 97
Konsep diri mempunyai tiga hal utama
yaitu Mind, Self, dan Society. Mind bagaimana
individu melihat dan memahami dirinya
dalam penelitian ini bagaimana wanita karir
melihat dirinya, kemudian Self bagaimana
individu atau wanita karir berperilaku
melihat dirinya seperti orang lain yang
dianggap dekat. Selanjutnya Society,
bagaimana individu atau wanita karir
berperilaku dipengaruhi oleh lingkungan
sekitarnya. Mind, Self, dan Society inilah
sedikit banyaknya merubah fokus penelitian
yang tadinya wanita karir menjadi konsep diri
wanita karir.
Pandangan mind, self, dan society sebagai
unsur dari konsep diri wanita karir mesti
dilihat dalam satu kesatuan. Tidak
terpisahnya tiga unsur tersebut dalam
individu berarti membawa perspektif penting
dalam kehidupan atau interaksi sosial
terutama dalam keluarga. Maka keluarga
tidak bisa lepas dari konstruksi konsep diri
wanita karir. Konteks ini akan
memperlihatkan bagaimana seorang wanita
yang berkarir menyeimbangkan
kehidupannya di ranah profesionalitas dengan
kehidupan berkeluarga. Untuk itu keluarga
menjadi sangat penting untuk mendukung
ataupun tidak mendukung dalam proses
seorang wanita dalam berkarir.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Wanita Karir dalam Perspektif
Komunikasi
Penelitian ini berfokus pada bagaimana
wanita karir berperilaku dalam keluarga dan
konsep diri wanita karir. Untuk itu, penting
memberikan satu pandangan dalam penelitian
mengenai wanita karir sebagai pelaku
komunikasi. Sebagai pelaku komunikasi,
wanita karir tidak terlepas dari interaksi sosial
dalam keluarga dan cara pandang wanita
karir pada dirinya sendiri. Menurut kamus
besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008
dalam Paputungan, 2011), wanita adalah
seorang perempuan atau kaum putri. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan kata
wanita karir bukan perempuan karir karena
mengikuti istilah umum yang lazim
dingunakan di Indonesia dan juga kata wanita
menduduki posisi dan konotasi terhormat.
Karir dalam arti umum ialah pekerjaan yang
memberikan harapan untuk maju. Selain itu,
kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat
atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir
berarti wanita yang bergerak dalam kegiatan
profesi baik usaha sendiri maupun ikut dalam
suatu perusahaan.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya,
dalam perspektif komunikasi wanita karir bisa
diidentifikasi sebagai pelaku komunikasi yaitu
pemahaman komunikasi dengan segala
praksisnya merupakan proses keseharian
manusia. Komunikasi tidak bisa dipisahkan
dari seluruh proses kehidupan konkret
manusia, aktivitas komunikasi merupakan
aktivitas manusiawi. Posisi manusia dalam
komunikasi, dapat dilihat pada rumusan
komunikasi dari Laswell dan Aristoteles. Pola
komunikasi menurut Laswell mengikuti
rumusan ”Who say what to whom in what
channel with what effect” bahwa cara yang
tepat untuk menerangkan suatu tindakan
komunikasi ialah menjawab pertanyaan
“Siapa yang menyampaikan, Apa yang
disampaikan, melalui saluran apa, kepada
siapa, dan apa pengaruhnya”. Sedangkan
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 98
dalam model komunikasi Aristoteles,
kedudukan manusia sebagai pelaku
komunikasi meliputi pandangan. Rumusan
komunikasi menurut Aristoteles sendiri terdiri
dari tiga unsur yakni, pembicara, argumen
dan pendengar (Cangara, 2014:21).
2. Analisis Interaksionisme Simbolik
Interaksionisme simbolik didasarkan pada
ide-ide mengenai diri dan hubungannya
dengan masayarakat. Karena ide ini dapat
diinterpretasikan secara luas. Ralph LaRossa
dan Donald C.Reitzes (West dan Turner,
2009:98) Telah mempelajari teori
interaksionisme simbolik yang berhubungan
dengan kajian mengenai keluarga. Mereka
mengatakan bahwa tujuh asumsi mendasari
interaksi simbolik dan bahwa asumsi-asumsi
memperlihatkan tiga tema besar.
Tema ketiga pada Interaksionisme
simbolik berfokus pada pentingnya konsep
diri (self-concept), interaksionisme simbolik
sangat tertarik dengan cara orang
mengembangkan konsep diri. Interaksionisme
simbolik menggambarkan individu dengan
diri yang aktif, didasarkan pada interaksi
sosial dengan orang lainnya. Pada tema
konsep diri memiliki dua asumsi tambahan
oleh LaRossan dan Reitzes yaitu, Individu-
individu mengembangkan konsep diri melalui
interaksi dengan orang lain. Asumsi tersebut
menyatakan bahwa kita membangun perasaan
akan diri (sense of self) tidak selamanya
melalui kontak dengan orang lain. Orang-
orang tidak lahir dengan konsep diri; mereka
belajar tentang diri mereka melalui interaksi.
Buku yang menjabarkan pemiikiran Mead
berjudul Mind, Self dan Society. Judul buku
tersebut merefleksikan tiga konsep penting
dari Interaksionisme Simbolik. Tiap konsep
akan dijabarkan dengan menekankan
bagaimana konsep penting lainnya
berhubungan dengan tiga konsep dasar
sebelumnya (West dan Turner, 2009:103).
3. Mind, Self, dan Society
Mead (West dan Turner 2009:104)
mendefinisikan pikiran (mind) sebagai
kemampuan untuk menggunakan simbol
yang mempunyai makna sosial yang sama dan
Mead percaya bahwa manusia harus
mengembangkan pemikiran melalui interaksi
dengan orang lain. Dengan menggunakan
bahasa dan berinteraksi dengan orang lain,
kita mengembangkan apa yang dikatakan
Mead sebagai pikiran, dan ini membuat kita
mampu menciptakan setting interior bagi
masyarakat yang kita lihat berprofesi di luar
diri kita. Jadi, pikiran dapat digambarkan
sebagai cara orang menginternalisasi
masyarakat. Akan tetapi, pikiran tidak hanya
tergantung pada masyarakat. Mead
menyatakan bahwa kedua mempunyai
hubungan timbal balik.
Mead (West dan Turner 2009:105) juga
menyatakan bahwa pengambilan peran
adalah sebuah tindakan simbolis yang dapat
membantu menjelaskan perasaan kita
mengenai diri dan juga memungkinkan kita
untuk mengembangkan kapasitas untuk
berempati dengan orang lain. Dengan kata
lain, secara sederhana Mind dalam konteks
penelitian ini adalah wanita karir di kota Palu
berperilaku sesuai pemikirannya sendiri.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 99
Mead (West dan Turner 2009:106)
mendefinisikan diri (self) sebagai kemampuan
untuk merefleksikan diri kita sendiri dari
perspektif orang lain. Ketika Mead berteori
mengenai diri, Ia mengamati bahwa melalui
bahasa orang mempunyai kemampuan untuk
menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri.
Sebagai subjek, kita bertindak, dan sebagai
objek, kita mengamati diri kita sendiri
bertindak. Mead menyebut subjek, atau diri
yang bertindak, sebagai I dan objek, atau diri
yang mengamati, adalah Me. I bersifat
spontan, implusif, dan kreatif, sedangkan Me
lebih reflektif dan peka secara sosial. I
mungkin berkeinginan untuk pergi keluar dan
berpesta setiap malam, sementara Me
mungkin lebih berhati-hati dan menyadari
adanya pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan ketimbang berpesta. Mead
melihat diri sebagai sebuah proses yang
mengintegrasikan antara I dan Me (West dan
Turner 2009:108). Pada konteks wanita karir di
Kota Palu self yaitu wanita karir berperilaku
melihat dirinya seperti orang lain yang
dianggapnya dekat.
Mead mendefinisikan masyarakat
(society) sebagai jejaring hubungan sosial yang
diciptakan manusia. Individu-individu terlibat
di dalam masyarakat melalui perilaku yang
mereka pilih secara aktif dan sukarela.
Masyarakat, karenanya terdiri atas individu-
individu, dan Mead berbicara mengenai dua
bagian penting masyarakat yang
mempengaruhi pikiran dan diri. Pemikiran
Mead mengenai orang lain secara khusus
(particular others) merujuk pada individu-
individu dalam masyarakat yang signifikan
bagi kita. Orang-orang ini biasanya adalah
anggota keluarga, teman dan kolega di tempat
kerja serta supervisor. Identitas dari orang lain
secara khusus dan konteksnya mempengaruhi
peerasaan akan penerimaan sosial kita dan
rasa mengenai diri kita. Sering kali
pengaharapan dari beberapa particular others
mengalami konflik dengan orang lainnya.
Pada konteks wanita karir di kota Palu,
masyarakat (society) dapat mempengaruhi
wanita karir dalam berperilaku.
4. Konsep Diri
Konsep diri menurut William D. Brooks
(dalam Rakhmat, 2012:98) adalah pandangan
dan perasaan kita tetntang diri kita. Ia
mengemukakan dua komponen dari konsep
diri yaitu komponen kognitif (self image) dan
komponen afektif (self esteem). Komponen
kognitif (self image) merupakan pengetahuan
individu tentang dirinya yang mencakup
pengetahuan “who am I”, dimana hal ini akan
memberikan gambaran sebagai pencitraan
diri. Adapun komponen afektif merupakan
penilaian individu terhadap dirinya yang akan
membentuk bagaimana penerimaan diri dan
harga diri individu yang bersangkutan.
5. Dimensi Konsep Diri
Calhoun dan Acocella (Istamala, 2012:17)
Konsep diri memiliki tiga dimensi yaitu
pengetahuan tentang diri sendiri,
pengharapan tentang diri sendiri dan
penilaian tentang diri sendiri.
a. Pengetahuan
Dimensi pertama dari konsep diri
adalah mengenai apa yang individu
ketahui mengenai dirinya. Individu di
dalam benaknya terdapat satu daftar
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 100
yang menggambarkan dirinya,
kelengkapan atau kekurangan fisik,
usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku,
pekerjaan, agama dan lain-lain.
b. Pengharapan
Pengharapan tentang diri kita tidak
terlepas dari kemungkinan kita
menjadi apa dimasa yang akan
datang. Individu mempunyai harapan
bagi dirinya sendiri untuk menjadi
ideal. Beberapa faktor yang
mempengaruhi ideal diri, adalah :
1) Kecenderungan individu untuk
menetapkan ideal diri pada batas
kemampuannya.
2) Faktor budaya akan mempengaruhi
individu dalam menetapkan ideal diri,
yang kemudian standar ini
dibandingkan dengan standar
kelompok teman.
3) Ambisi dan keinginan untuk melebihi
dan berhasil, kebutuhan yang
realistis, keinginan untuk
menghindari kegagalan, perasaan
cemas dan rendah diri.
c. Penilaian
Individu berkedudukan sebagai
penilai tentang dirinya sendiri.
Apakah bertentangan dengan
pengharapan individu dan standar
bagi individu Nur Ghufron, dkk
(Istamala, 2012:17).
6. Komunikasi dan Interaksi dalam Keluarga
Keluarga adalah dua atau lebih dari dua
individu yang bergabung karena hubungan
darah, hubungan perkawinan atau
pengangkatan dan mereka hidup dalam satu
rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan
di dalam perannya masing-masing
menciptakan serta mempertahankan
kebudayaan. Berkomunikasi itu tidak mudah,
terkadang seseorang dapat berkomunikasi
dengan baik kepada orang lain. Di lain waktu
seseorang mengeluh tidak dapat
berkomunikasi dengan baik kepada orang
lain. Ketika dalam keluarga dua orang
berkomunikasi, sebetulnya mereka berada
dalam perbedaan untuk mencapai kesamaan
pengertian dengan cara mengungkapkan
dunia sendiri yang khas, mengungkapkan
dirinya yang tidak sama dengan siapapun.
Sekalipun yang berkomunikasi ibu adalah
antara suami dan istri antara ayah dan anak
antara ibu dan anak, dan antara anak dan
anak. Hanya sebagian kecil mereka itu sama-
sama tahu, sama-sama mengalami, sama
pendapat dan sama pandangan (Syaiful,
2004:11).
C. Konseptualisasi Penelitian
Sesuai fokus masalah penelitian, maka
penelitian ini menggunakan tipe penelitian
deskriptif kualitatif. Konsep dalam penelitian
ini adalah konsep yang langsung menjelaskan
tentang Konsep Diri Wanita Karir dalam
Keluarga. Subjek penelitian ini adalah ibu
rumah tangga yang juga bekerja secara
profesional yaitu Ibu Ika Pamounda yang
berprofesi sebagai Custumer Service di Bank
Danamon cabang Palu, Ibu Nurfadilah yang
berprofesi sebagai Sales Manager di Carrefour,
Ibu Farida Batjo yang berprofesi sebagai
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 101
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Palu, Ibu Ni
Made Puspayanti yang berprofesi sebagai
Manager di Hypermart dan Ibu Cherly Trisna
Ilyas yang berprofesi sebagai Kepala Sub
Bagian Hukum KPU Sulawesi Tengah. Objek
dari penelitian yang akan dikaji adalah
Konsep Diri Wanita Karir dalam Keluarga.
Reduksi data dilakukan pertama kali
dengan menyusun data hasil wawancara
dalam bentuk deskripsi dan memilah
informasi yang telah didapat, selanjutnya
dikemas dalam penyajian data. Melalui
penyajian data tersebut, maka data yang
terorganisasi dan terkategori kemudian
disimpulkan yang berupa data temuan
sehingga mampu menjawab pertanyaan dari
penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari data
yang telah direduksi dan disajikan dalam
penyajian data adalah keseluruhan informan
memberikan jawaban yang memiliki
permasalahan yang berbeda-beda mengenai
konsep diri wanita karir dalam keluarga.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh dari lapangan, maka akan dibahas
secara deskriptif mengenai konsep diri dan
aktivitas wanita karir dalam keluarga, temuan
peneliti tersebut sekaligus akan menjadi fokus
penelitian ini. untuk memberikan pemaparan
secara deskriptif maka telah dilakukan
wawancara mendalam kepada informan
terkait, untuk menjadi tolok ukur dalam
menganalisis seperti apa konsep diri wanita
karir dalam keluarga dengan menggunakan
teori interaksionisme simbolik.
Pada konteks penelitian ini wanita karir di
kota Palu memiliki pandangan mengenai
sosok wanita karir yang ideal, mereka menilai
diri mereka yang tentunya tidak terlepas dari
rangsangan sosial dan interaksi dengan orang
lain, mereka memaknai menjadi wanita karir
harus dapat menjalankan peran sebagai ibu
rumah tangga dan juga sebagai wanita karir,
walaupun bekerja wanita karir tetap mampu
melaksanakan tangggungjawab utamanya
sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian,
dari kelima informan memaknai profesi
mereka bukanlah suatu kesalahan apabila Ia
tahu apa tujuannya dalam berkarir,
memegang komitmen, bisa memposisikan diri
ketika berada di rumah maupun di kantor
serta mendapat dukungan keluarga.
Beberapa diantara mereka menafsirkan
diri mereka sebagai sosok yang lebih telaten
dalam mengurus rumah tangga walaupun
disibukkan dengan pekerjaan. Menurut
mereka walaupun dirinya bukan ibu rumah
tangga seutuhnya, namun mereka punya
kemampuan dalam mengurus rumah tangga.
Informan juga mengaku kehidupan sehari-hari
mereka harus pandai mengatur waktu agar
semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
Hal ini didukung dengan pernyataan Mead
(dikutip dari West dan Turner, 2009:104)
mendefinisikan mind sebagai kemampuan
individu dalam menggunakan simbol yang
memiliki makna sosial dan kemampuan
tersebut berkembang dengan adanya interaksi
yang dilakukan.
Menurut mereka, seperti pada umumnya
orang yang telah selesai kuliah yang
dilakukan selanjutnya ialah mencari pekerjaan
sehingga informan pun melakukan hal yang
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 102
sama. Keinginan untuk mendapatkan
pekerjaan sebagai bentuk memanfaatkan
kemampuan diri, selain itu juga bisa
memenuhi kebutuhan ekonomi. Empat dari
lima informan punya keinginan untuk
berkarir karena melihat ibunya sendiri yang
juga berkarir. Mereka lahir dan dibesarkan
dari keluarga yang juga berkarir, sehingga
mereka telah terbiasa dengan lingkungan
seperti itu dan memotivasi informan untuk
menjadi wanita karir.
Mereka menjadikan sosok “ibunya”
sebagai panutan dalam menjalankan peran
sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir.
lingkungan terdekat yaitu lingkungan
keluarga yang mempengaruhi diri informan
untuk berkarir karena informan lahir dari
keluarga yang berlatar belakang berkarir,
sehingga dirinya terdorong untuk menjalani
kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan
juga wanita karir. Sehingga self pada konteks
penelitian ini yakni wanita karir berperilaku
melihat dirinya seperti orang lain yang
dianggapnya dekat dan didukung pernyataan
Mead (West dan Turner, 2009:106) yang
menjelaskan diri (self) sebagai kemampuan
untuk merefleksikan diri kita sendiri dari
perspektif orang lain.
Berdasarakan hasil temuan dilapangan
beberapa diantara informan memiliki konsep
diri berbeda ketika sebagai wanita karir dan
ketika sebagai ibu rumah tangga. Konsep
“Me” adalah ketika informan berprofesi
sebagai wanita karir mereka menjalankannya
secara professional, berpenampilan menarik
dan memiliki kekuasaan karena adanya
jabatan. Namun, ketika informan tidak lagi
berperan sebagai wanita karir yaitu konsep “I”
mereka memiliki konsep diri yang sama.
Informan kembali kerumah mereka kembali
menjadi seorang istri yang tunduk dan patuh
kepada suami. Mereka kembali menjalani
kodratnya sebagai ibu rumah tangga
Memasak makanan buat keluarga serta
mengurus suami dan anaknya. Sehingga
konsep Self pada penelitian ini juga adanya
kemampuan untuk menjadi subjek dan objek
bagi dirinya sendiri.
Dari hasil temuan data yang telah
diuraikan dapat dilihat bahwa kelima
informan memiliki pandangan positif
terhadap dirinya. Informan senang dan
nyaman menjadi wanita karir sehingga
memiliki keyakinan terhadap pilihannya
menjalani peran ganda yang didasarkan oleh
komitmen dan kesadaran akan
tanggungjawab utamanya sebagai ibu rumah
tangga. Mendapat dukungan penuh dari
keluarga informan jadikan motivasi dalam
menjalani peran gandanya, kekurangan yang
dimiliki saat menjalani kedua peran tersebut
dijadikan pembelajaran dan tidak lupa selalu
berkomunikasi dengan pasangan jujur dan
terbuka terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi.
Konsep diri yang positif berperan
terhadap interaksi informan dengan orang
lain. Informan yang dapat dipercaya oleh
lingkungan kerjanya dan juga selalu
mendapat dukungan dari keluarga. Hal
tersebut membuat informan lebih mudah
berinteraksi dengan orang-orang lain
disekitarnya dan menumbuhkan rasa percaya
diri sehingga dapat berbaur dengan
lingkungan sekitarnya. Sebagian dari mereka
merasa senang dan nyaman menjalani
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 103
perannya sebagai ibu rumah tangga maupun
sebagai wanita karir. Konsep diri seseorang
terbentuk karena adanya interaksi yang
dilakukan dengan orang disekitarnya.
Semakin sering terjadinya interaksi yang
dilakukan semakin banyak pengalaman-
pengalaman yang didapat oleh individu.
Dalam teori interaksionisme simbolik George
Herbert Mead (dikutip dari West dan Turner,
2009:104) menyatakan faktor society
merupakan salah satu yang mempengaruhi
konsep diri seseorang.
Kelima informan memiliki harapan-
harapan yang berbeda-beda dalam berkarir,
Ibu Yanti yang memiliki harapan besar
kedepannya bisa berkarir sesuai bidang
ilmunya. Kemudian Ibu Ika dan Ibu Cherly
memiliki harapan untuk bisa menduduki
jabatan tertinggi di tempatnya bekerja, ibu
Farida ingin terus berkarir dan bisa
bermanfaat bagi orang banyak. Hal tersebut
dilakukan dengan cara menikmati setiap
proses yang ada dan menggapai apa yang
mereka harapkan, sehingga pada akhirnya
mereka akan melakukan penilaian terhadap
dirinya apakah dengan adanya pengetahuan
dan harapan yang mereka miliki saling
mendukung atau tidak.
Seperti yang telah diketahui bahwa setiap
individu akan bertingkah laku sesuai konsep
diri yang dimilikinya. Dalam konteks
penelitian ini, wanita karir adalah pelaku
komunikasi terhadap dirinya maupun
lingkungan sosialnya. Menjalankan peran
sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita
karir merupkan keseharian dari aktivitas
informan. Aktivitas dalam konteks ini ialah
aktivitas wanita karir ketika berada di ranah
keluarga dan berada di luar rumah.
Peran ganda yang dijalani oleh informan
setiap harinya, membuat informan harus
pandai dalam mengatur waktu. Peran
informans ebagai istri dan ibu tidaklah
mudah. Meskipun pekerjaan mengurus rumah
tangga, melayani suami dan merawat serta
mendidik anak bukanlah kegiatan produktif
secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut
sangatlah penting artinya bagi kehidupan
anggota keluarga. Semua informan
menjalankan rutinitas setiap harinya dengan
merencanakan dan menyusun apa-apa yang
mesti Ia lakukan ketika pagi hari sampai Ia
menjalankan tugasnya di kantor.
Pada hasil penelitian yang telah
dijabarkan di atas, informan melakukan hal
tersebut agar mereka bisa mengerjakan
aktivitasnya di rumah. Mengurus anak dan
suami, menyiapkan kebutuhan suami dalam
bekerja misalnya baju, sepatu dan lain-lain
dan juga menyiapkan makanan buat anak dan
suaminya. Sehingga ketika mereka pergi
bekerja segala urusan mengenai rumah tangga
telah terselesaikan dan mereka tidak terlambat
untuk masuk kantor. Manajemen waktu
adalah strategi penting yang perlu diterapkan
oleh para pekerja perempuan yang sudah
berkeluarga untuk dapat mengoptimalkan
perannya sebagai ibu rumah tangga, istri dan
sekaligus pekerja (Rini, 2002).
Menjalani kehidupan sehari-hari dengan
banyaknya aktivitas di luar rumah berdampak
pada kurangnya waktu yang dihabiskan
bersama keluarga. Terlebih ketika sang ibu
juga memutuskan untuk bekerja, sehingga
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 104
timbulnya kebutuhan akan perlunya quality
time pada keluarga dan hal itu benar terasa
ketika di hari weekend dan libur kerja.
Meluangkan waktu bersama suami dan anak
merupakan momen yang berharga bagi
informan, karena dimomen itu informan
mempunyai kesempatan untuk saling berbagi,
belajar dan memahami satu sama lain antar
anggota keluarga dengan lebih santai. Di
momen itu juga informan bisa merasakan
menjadi seorang ibu seutuhnya bagi anak dan
suaminya dan juga quality time bersama
keluarga merupakan momen untunk
merefreshkan kembali pikiran-pikiran serta
semakin mengeratkan hubungan informan
bersama keluarga.
E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan tentang “Konsep Diri Wanita
Karir dalam Keluarga (Studi Kasus pada Ibu
Rumah Tangga yang Bekerja Penuh di Kota
Palu)” maka peneliti dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut. Aktivitas wanita
karir dalam kmenjalani perannya ialah ketika
wanita karir berada di rumah sebagian besar
dari wanita karir memberi batasan-batasan
terhadap urursan kantor. Ketika berada di
rumah wanita karir hanyalah seorang ibu
rumah tangga seperti biasanya mengurus
anak, melayani suami dan mengerjakan
pekerjaan rumah tangga. Para wanita karir
selalu menjadwalkan apa saja saja yang mesti
mereka lakukan agar tugas sebagai ibu rumah
tangga dan pekerjaan bisa berjalan dengan
baik. Berbagi peran dalam keluarga juga
mereka lakukan bersama pasangan seperti
mengerjakan pekerjaan rumah ataupun dalam
hal mengurus anak. Sebagian diantara mereka
juga memberi batasan ketika berada di luar
rumah atau ketika bekerja. Ketika sedang
bekerja, mereka fokus pada pekerjaan sampai
waktu pulang tibaa, sebagian kecil dari
mereka bisa menjalankan peran sebagai ibu
rumah tangga ketika masih pada waktu
bekerja. Pilihan untuk menjadi seorang wanita
karir tidak serta merta begitu saja dilakukan
dan dijalani oleh informan, dukungan
maupun penolakkan yang diperolehnya
sudah sering didapatkan dilingkungan
sosialnya. Dorongan informan dalam berkarir
ialah karena adanya kebutuhan, mereka
bekerja untuk menambah pemasukan suami
selain itu mereka senang dan nyaman
menjalani peran gandanya selama ini. Konsep
diri wanita karir dalam keluarga terbentuk
atas interaksi dengan lingkungan sosialnya
yang pertama adanya pandangan dari diri
sendiri mengenai wanita karir yang ideal,
walaupun merasa belum ideal karena
terkadang belum maksimal dalam
menjalankan perannya sebagai ibu rumah
tangga namun wanita karir tetap berusaha
untuk menjalankan peran ganda tersebut.
Selalu terbuka dan jujur terhadap pasangan,
membuat wanita karir selalu mendapat
dukungan dari keluarga. Sebagian besar
wanita karir merasa nyaman dan dan senang
menjalankan peran gandanya dan tidak ingin
untuk berhenti bekerja, wanita karir melihat
sosok ibunya dalam menjalankan peran
gandanya karena sebagian besar diantara
mereka lahir dan sibesarkan oleh ibu yang
juga berkarir. Dalam menjalankan peran
gandanya, wanita karir sangat didukung oleh
keluarganya hal tersebut dijadikan motivasi
bagi wanita karir dalam menjalankan peran-
perannya. Sebagian dari wanita karir masih
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JH/index 105
mendapatkan pandangan negatif dari
lingkungannya terhadap keputusannya
menjadi ibu rumah tangga dan juga wanita
karir dan sebagian lainnya mendapat
dukungan dan kepercayaan dari lingkungan
sosial sekitarnya.
Daftar Pustaka
Calhoun, F. & Acocella. 1990. Psikologi
Tentang Penyesuaian dan Hubungan
Kemanusiaan (edisi ketiga). Semarang:
Penerbit IKIP Semarang
Cangara, Hafied. 2014. Pengantar Ilmu
Komunikasi Edisi Kedua. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Rakhmat, Jalaludin. 2012. Psikologi
Komunikasi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Rini, Agatha. 2002. Konflik Kerja Karyawan
BPR Studi Kasus Perbarido Komda
Semarang. Dian Ekonomi Vol.VII No.1,
Semarang.
Syaiful, B Djamarah. 2004. Pola Komunikasi
Orang Tua dan Anak dalam Keluarga.
Jakarta: Bineka Cipta
West, Richard dan Tumer, Lynn. 2009.
Pengantar teori Komunikasi: Analisis
dan Aplikasi. Jakarta: Salemba
Humanika