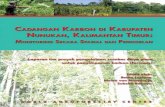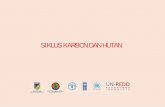PERSAMAAN ALLOMETRIK BIOMASSA DAN KARBON UNTUK PENDUGAAN SIMPANAN KARBON DALAM MENDUKUNG UPAYA...
Transcript of PERSAMAAN ALLOMETRIK BIOMASSA DAN KARBON UNTUK PENDUGAAN SIMPANAN KARBON DALAM MENDUKUNG UPAYA...
JURNAL SOSEK Vol. 10 No. 2 Hal 75 - 139Bogor2013
ISSN1979-6013
Volume 10 Nomor 2, Juni Tahun 2013
ISSN: 1979-6013TERAKREDITASI
No. 493/AU1/P2MI-LIPI/08/2012
Forestry Socio and Economic Research Journal
KEMENTERIAN KEHUTANAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
Ministry of Forestry
Centre for Climate Change and Policy Research and Development
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
BOGOR INDONESIA
Forestry Research and Development Agency
JU
RN
AL
PE
NE
LIT
IAN
SO
SIA
LD
AN
EK
ON
OM
IK
EH
UTA
NA
NV
ol.
10
No
.2
Ju
niTah
un
2013
(Fo
restry
So
cio
an
dE
co
no
mic
Researc
hJo
urn
al)
Volume 10 Nomor 2, Juni Tahun 2013
ISSN: 1979-6013
Forestry Socio and Economic Research Journal
SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN
PENELITIANJURNAL
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.742/E/2012 dengan kategori B. Memuat Karya Tulis Ilmiah dari hasil-hasil penelitian di bidang Sosial dan EkonomiKehutanan serta lingkungan dan terbit secara berkala empat kali dalam setahun (April, Juni, September, Desember).
Penanggung Jawab ( ) : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakanDewan Redaksi ( )
Sekretariat Redaksi ( )Ketua ( ) : Kabid Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian
Anggota ( ) : 1. Kasub Bid Data, Informasi dan Diseminasi
3. Leni Wulandari, S.Hut4. Ratna Widyaningsih, S.Kom
Mitra Bestari ( ) : 1. Prof. Dr. Dudung Darusman (Kebijakan Kehutanan)2. Prof. Dr. Djaban Tinambunan (Keteknikan Kehutanan)3. Prof.MustofaAgungSardjono(PerhutananSosial)4. Dr. A. Ngaloken Gintings, (Konservasi Tanah dan Air)5. Dr. Ir. Boen M. Purnama (Ekonomi Sumberdaya Hutan)6. Prof. Dr. Ir. Kurniatun Hairiah (Perhitungan Emisi Karbon dan Upaya
Pengendalian Perubahan Iklim)
Diterbitkan oleh ( ) :Pusat n( )Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan( )Alamat ( ) : Jalan Gunung batu No. 5, PO. BOX 272 Bogor 16610, IndonesiaTelepon ( ) : 62-0251-8633944Fax ( ) : 62-251-8634924Email : [email protected]
Forestry Social and Economic Journal is an accredited journal. Based on the decree of Director of Indonesian Science Institute (LIPI)No. 742/E/2012. This Journal Publishes result of research in Socioeconomic Forestry and released four times annually (April, June,September, December).
Editor in ChiefEditorial Board
Editorial SecretariatChairman
Members
Peer Reviewers
Published by
Forestry Research and Development AgencyAddressPhone
Fax
Ketua ( ) : Dr. Ir. Hariyatno Dwiprabowo, M.Sc (Ekonomi Kehutanan)Anggota ( ) : 1. Dr. Ir. Satria Astana, M.Sc (Ekonomi Kehutanan)
2. Ir. Subarudi, M.Wood.Sc (Sosiologi Kehutanan)3. Ir. Setiasih Irawanti, M.Sc (Ekonomi Kehutanan)4. Prof. Irsal Las (Agroklimatologi dan Lingkungan)5. Dr. Ir. Didik Suhardjito, M.S (Sosiologi, Kehutanan & Kehutanan
Masyarakat)6. Dr. Herman Hidayat (Studi dan Kemasyarakatan)7. Dr. Ir. Handewi P. Salim (Sosial Ekonomi Pertanian)8. Drs. Edi Basuno, M.Phill, P.Hd (Sosial Ekonomi Pertanian)
2. Bayu Subekti, SIP, M.Hum
ChairmanMembers
Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan KebijakaCentre For Climate Change And Policy Research And Development
PETUNJUK PENULISAN NASKAH“JURNAL
1. Judul, harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas tidak lebih dari 2 baris, ditulis dengan TimesNew Roman font 14 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-30 halaman, 2 spasi, ukuran kertas A4 dan font ukuran huruf 12.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, dicantumkan pula alamat instansi,No. Telp/faks serta alamat e-mail penulis (jika ada).
4. /abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indoneisa, tidak lebih dari 200 kata, berisi intisaripermasalahan secara menyeluruh, bersifat informatif mengenai hasil yang dicapai, diketik dengan font10, spasi satu.
5. /Kata kunci ditulis di bawah abstrak dan tidak lebih dari lima entri.
6. Tubuh naskah, diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten sesuai dengan kebutuhan. Semua nomorditulis rata dibatas kiri tulisan, seperti:I, II, III, dst. untuk BabA, B, C, dst. untuk Sub Bab1, 2, 3, dst. untuk Sub subbaba, b, c, dst. untuk Sub sub subbab
7. Sistematik Penulisan adalah sebagai berikut:Judul : Bahasa Indonesia dan InggrisAbstract : Bahasa InggrisAbstrak : Bahasa IndonesiaI. PendahuluanII. Bahan dan MetodeIII. Hasil dan PembahasanIV. Kesimpulan dan SaranDaftar Pustaka
8. Tabel, gambar, grafik dan sejenisnya diberi nomor, judul dan keterangan dalam bahasa Indonesia danInggris.
9. Daftar Pustaka merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah dan disajikan secara alphabetik namabelakang penulis pertama. Pustaka yang dirujuk diusahakan terbitan paling lama sepuluh tahun terakhir.Pustaka dapat berasal antara lain dari buku, jurnal, prosiding dan internet, dengan contoh cara penulisansebagai berikut:- Gidden, A. 1979. Central problems in social theory. Macmillan. London.- Doornbos, M. and L. Gertsch. 1994. Sustainability, technology and corporate interest: resources
strategies in India's modern diary sector. development Studies 30(3):916-50- Purnomo. 2004. Potensi dan peluang usaha perlebahan di propinsi Riau. Prosiding ekspose hasil-
hasil Litbang Hasil Hutan, tanggal 14 Desember 2004 di Bogor. Hlm. 133-141 Pusat LitbangHasil Hutan. Bogor.
Abstract
Key words
- Agarwal, A. and S. Narain. 2002. Community and water management : the key to environmentregeneration and proverty allevation. diakses 14 Januari 2002 dari Website: http://www.undp.org/seed/pei/publication/ water.pdf. diakses 14 Januari 2002
PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN”
JURNAL SOSEK Vol. 10 No. 2 Hal 75 - 139Bogor2013
ISSN1979-6013
Volume 10 Nomor 2, Juni Tahun 2013
ISSN: 1979-6013TERAKREDITASI
No. 493/AU2/P2M-LIPI/08/2012
Forestry Socio and Economic Research Journal
KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
BOGOR INDONESIA
Ministry of Forestry
Forestry Research and Development Agency
Centre for Climate Change and Policy Research and Development
Ucapan Terima Kasih
Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan mengucapkan terima kasih danpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra bestari ( ) yang telah menelaah naskah yangdimuat pada edisi Vol. 10 No. 2 Juni tahun 2013 :
peer reviewers
1. Prof. Dr. Dudung Darusman2. Prof. Mustofa Agung Sardjono3. Dr. Haruni Krisnawati, M.Sc.
DAFTAR ISI
PERSAMAAN ALLOMETRIK BIOMASSA DAN KARBON UNTUKPENDUGAAN SIMPANAN KARBON DALAM MENDUKUNG UPAYAKONSERVASI SAVANA
)Dhany Yuniati & Hery Kurniawan .................................................................................
ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTANKEMASYARAKATAN (Hkm)
Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum & Eno Suwarno ...........................................
CADANGAN KARBON HUTAN LINDUNG LONG KETROK DIKABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR UNTUKMENDUKUNG MEKANISME REDD+
)Yonky Indrajaya ................................................................................................................
P E R A N H U K U M A DAT DA L A M P E N G E L O L A A N DA NPERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARABARAT DAN DESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR
Magdalena ........................................................................................................................
PENGARUH DINAMIKA SPASIAL SOSIAL EKONOMI PADA SUATULANSKAP DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERHADAPKEBERADAAN LANSKAP HUTAN (STUDI KASUS PADA DASCITANDUY HULU DAN DAS CISEEL, JAWA BARAT)
)Edy Junaidi, Retno Maryani .............................................................................................
CORYPHA UTAN (Biomass and Carbon AllometricEquation for Estimating Carbon Stock to Support Corypha utan Savanna Conservation
(Learning Organization and Policy Implementation ofCommunity Forest)
(Carbon Stocks of Protection Forest inMalinau District, East Kalimantan to Support REDD+ Mechanism
(The Roles ofCustomary Law in Forest Management and Protection in Sesaot Village, West Nusa Tenggaraand Setulang Village, East Kalimantan)
(Effect of SpatialDynamics of Socio-Economic in the Watershed Landscape Toward The Existence of the ForestLandscape; Case Studies on Citanduy Hulu Watershed and Ciseel Watershed, West Java
75 - 84
85 - 98
99 - 109
110 - 121
122 - 139
ISSN: 1979-6013TERAKREDITASI
No. 493/AU2/P2M-LIPI/08/2012
Forestry Socio and Economic Research Journal
Volume 10 Nomor 2, Juni Tahun 2013
JURNAL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KEHUTANAN
ISSN: 1979 - 6013 Terbit : Juni 2013
Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini bolehdiperbanyak tanpa ijin dan biaya.
UDC (OSDCF) 630*161.32Dhany Yuniati & Hery Kurniawa
Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk PendugaanSimpanan Karbon dalam Mendukung Upaya Konservasi Savana
Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2,hal. 75 - 84
Gewang ( ) merupakan jenis tanaman yang unik karenafungsinya sebagai sumber pangan, minuman, bahan bangunan(rumah, pagar, kandang) dan industri sederhana rumah tangga.Pemanfaatan oleh masyarakat dilakukan dengan penebanganpohon-pohon yang produktif sehingga mengancam kelestariantanaman gewang. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)merupakan daerah sebaran alami yang potensial bagi pohongewang. Di sisi lain tegakan gewang juga memiliki fungsi sebagaipenyerap dan penyimpan karbon, sehingga keberadaan tegakandan proses permudaan perlu dijaga sejalan dengan upaya untukmeningkatkan simpanan karbon hutan savana di NTT. Informasimengenai kandungan karbon dalam gewang menjadi pentingkarena dengan informasi tersebut dapat diketahui ukuran yangpaling layak bagi gewang untuk ditebang dan dimanfaatkan. Sampaisaat ini belum ada persamaan allometrik yang khusus dikembangkanuntuk pendugaan potensi simpanan karbon pada savana gewang( ). Penyediaan data dengan tingkat kerincian ( ) 3memerlukan pendugaan cadangan karbon yang dimulai daripendugaan biomassa dan karbon dengan menggunakanyang spesifik terhadap spesies dan tempat ( ). Tulisan inimengemukakan model persamaan allometrik untuk pendugaanbiomassa pada tanaman gewang ( ) dengan metodedestruktif . Disamping itu dikemukakan pula modelpersamaan allometrik untuk pendugaan simpanan karbon padatanaman gewang ( ) dengan pengukuran langsungmenggunakan metode karbonasi atau pengarangan. Modelpersamaan allometrik untuk pendugaan biomasa batang tanamangewang ( ) y = 19703x , pendugaan biomasa daun y =8449x dan pendugaan biomasa pelepah y = 16855x . Hasilstudi menghasilkan model persamaan allometrik untuk pendugaankarbon secara langsung pada daun tanaman gewang ( ) y =10704x , pendugaan karbon secara langsung pada pelepah y =15069x dan pendugaan karbon secara langsung pada batang y =27110x .
Persamaan allometrik, biomassa, karbonkonservasi
Corypha Utan
Corypha utan
C. utan Tier
modellingsite
C. utansampling
C. utan
C. utan
C. utan
, Coryphautan,
1,735
0,680 0,491
0,721
0,946
1,823
Kata kunci:
UDC (OSDCF) 630*922.2Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum & Eno Suwarno
Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan HutanKemasyarakatan (HKm)
Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2,hal. 85 - 98
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintahdimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian aksesterhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secaralestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasibelajar ( ), organisasi pelaksana yang terlibatprogram Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitianyang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melaluiobservasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara scoring.Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dankepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukandi Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi ataumasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhankarakteristik organisasi pembelajar:
telah terjadi pada berbagaitingkat pada organisasi Hkm yang menjadi sampel. Figurkepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujuddengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuaikarakteristik organisasi pembelajar adalah dimana padaumumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan danmengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkmmasih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusipelaksana.
Hutan kemasyarakatan (Hkm), organisasi belajar,proses kebijakan
Learning Organization
system thinking, personal mastery,mental models, shared vision, team learning,
shared vision,
Kata kunci:
UDC (OSDCF) 630*914Yonky Indrajaya
Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di KabupatenMalinau, Kalimantan Timur untuk Mendukung MekanismeREDD+
Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2,hal. 99 - 109
Kegiatan konservasi hutan lindung (HL) melalui mekanismeREDD+ merupakan salah satu kegiatan yang sangat potensialuntuk dapat menurunkan emisi global. Menjaga HL dari kegiatandeforestasi dan degradasi hutan dapat mencegah hutan untukmengemisi karbondioksida. Informasi tentang jumlah cadangankarbon hutan lindung yang belum terganggu (hutan perawan)penting sebagai base line dan untuk mengetahui potensipenyerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensicadangan karbon yang tersimpan dalam biomassa tegakan hutanlindung Long Ketrok, yaitu hutan lindung yang dikelola oleh
masyarakat desa Setulang, Kabupaten Malinau, ProvinsiKalimantan Timur. Metode perhitungan cadangan karbon yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode non-destructivedengan menggunakan persamaan allometrik yang telah dibangundi hutan tropis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwajumlah karbon tersimpan dalam hutan lindung Long Ketrok adalah304 ton/ha yang terdiri dari karbon tersimpan dalam biomassa diatas permukaan tanah sebesar 255 ton/ha, biomassa akan sebesar42 ton/ha, dan nekromassa sebesar 7 ton/ha. Proporsi batang,cabang, akar, dan daun dalam biomassa karbon berturut-turutsebesar 70,7%, 14,6%, 14,1% dan 0,6%.
biomassa, karbon, hutan lindungKata kunci:
UDC (OSDCF) 630*931Magdalena
Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan diDesa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, KalimantanTimur
Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2,hal. 110 - 121
Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesiaseringkali berasal dari masyarakat lokal sekitar hutan. Sementaraitu, beberapa tulisan ilmiah beragumentasi bahwa pengelolaansecara adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaanhutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakatlokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutanserta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adatdalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang di-gunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yangdidominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulangyang didominasi Orang Dayak Kenyah (Kalimantan Timur).Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan danwawancara dengan 30 pegawai pemerintah, 20 LSM dan 50penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adatmasih berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari.
Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas,hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasanhak masyarakat terhadap hutan, transparansi dan akuntabilitaskeuangan.
pengelolaan dan perlindungan hutan, masyarakatlokal, hukum adat, faktor-faktor
Kata kunci:
UDC (OSDCF) 630*116Edy Junaidi & Retno Maryani
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi pada Suatu LanskapDaerah Aliran Sungai (DAS) Terhadap Keberadaan LanskapHutan (Studi Kasus Pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel,Jawa Barat)
Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2,hal. 122 - 139
Kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungansekitarnya, baik yang bersifat ekologis, ekonomis maupun sosial.Pengelolaan sumberdaya hutan perlu dilakukan denganberorientasi ekosistem secara keseluruhan. Oleh karenanya,rencana penataan tata guna hutan perlu pengelolaan di tingkatlanskap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanyahubungan timbal balik antara kondisi sosial ekonomi masyarakatyang berada di dalam wilayah suatu DAS dengan kondisilingkungan yang mempengaruhi terjadinya dinamika lanskaphutan. Metode untuk menentukan keeratan masing-masingkarakteristik (lingkungan dan sosial-ekonomi) dengan keberadaanhutan, menggunakan model(GWR) dengan melihat nilai korelasinya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor biofisik dan sosial ekonomi yangmempunyai korelasi yang kuat terhadap keberadaan lanskap hutanpada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel adalah (i) curah hujan,(ii) kelerengan, (iii) kepekaan tanah terhadap erosi, (iv) kerapatandrainase, (v) rata-rata lereng, (vi) kepadatan agraris dan (vii)ketegantungan terhadap lahan.
biofisik, sosial ekonomi dan lanskap hutan
Geographically Weighted Regression
Kata kunci:
FORESTRY SOCIO AND ECONOMIC RESEARCH JOURNAL
ISSN: 1979 - 6013 Date of issue : June 2013
The discriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproducedwithout permission or charge.
UDC (OSDCF) 630*161.32Dhany Yuniati Hery Kurniawan
Biomass and Carbon Allometric Equation for Estimating Carbon Stock toSupport Corypha utan Savanna Conservation
Forestry Socio Economic Journal Vol. 10 No. 2, p. 75 - 84
Gewang is a unique species for its function as source of food,drink,construction material house, fence, shed and home industry. Peopleutilize it by cutting down the growing productive trees, causing the sustainabilityof gewang becomes threatened. Province of Nusa Tenggara Timur (NTT) isnatural habitat for gewang distribution. On the other hand, standshave ability or function as carbon absorber and sinker also. Because of this, theexistence and regeneration process should be guarded as this function is in linewith the efforts to increase carbon stock of savanna forest in NTT. Informationof carbon sink in trees became important, because of with thisinformation could be understood the most feasible size/dimension of gewang tobe harvested. Up to now there is no allometric equation which is specificallydeveloped to estimate carbon stock potential on gewang's savanna . Inorder to provide data using of accuracy level 3 Tier 3 , carbon stock estimationwas done by estimating biomass and carbon, modell for specific species and site.This paper constructs allometric equation model for estimating gewang
biomass with destructive sampling method. In addition, allometricequation for estimating carbon stock of gewang was constructed by directestimation using carbonation method. The study result in allometric equation
model for estimating gewang stem biomass y = 19703x , for leaves biomass
y = 8449x and for midrib biomass y = 16855x . Allometric equation
model to estimate carbon stock for gewang leaves y = 10704 x , for midrib y
= 15069 x and for stem y = 27110 x .
Allometric equations, biomass, carbon, ,conservation
&
( )( )
( )( )
()
Corypha utan
Corypha utan
C. utan
C. utan
C. utan
C.utan
1.735
0.680 0.491
0.721
0.946 1.823
Keywords:
UDC (OSDCF) 630*922.2Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum Eno Suwarno
Learning Organization and Policy Implementation of Community Forest
Forestry Socio Economic Journal Vol. 10 No. 2, p. 85 - 98
The undertaking of community forest (Hkm) program by government is aimedat capacity development and access granting of local people in managing forestsustainably. The study aims to assess, through characteristics of learningorganization, the government executing institutions involving in Hkm programand Hkm policy implementation. Research method used was qualitativemethod by using observation, in-depth interview, document reading, and scoring
&
method. Method of analysis was discourse, actors or network and their interestsfollowing policy process approach. Study took place in South Sulawesi,Lampung and Nusa Tenggara Barat provinces. Research respondents wereindividual, group, agencies, and community. Results showed that fulfilment oflearning organization characteristics : system thinking, personal mastery,mental models, shared vision, team learning, has been achieved at differentdegrees in sampled agencies. Leadership in certain agency becomes crucial inorder learning organization to be well realized. Other critical factor in learningorganization realization is shared vision in which in general agencies havedifficulty in interpreting and implementing organization vision and mission.Hkm policy are still facing weakness in its implementation by executingagencies and community involved.
Community forest, learning organization, policy processKeywords:
UDC (OSDCF) 630*914Yonky Indrajaya
Carbon Stocks of Protection Forest in Malinau District, East Kalimantan toSupport REDD+ Mechanism
Forestry Socio Economic Journal Vol. 10 No. 2, p. 99 - 109
Conservation on protection forests through REDD+ mechanism is one of thepotential activities that can reduce global emission. Preserving protection forestfrom deforestation and forest degradation can prevent forests to emit carbondioxide. Information on carbon stocks in virgin forest is important for baselineand to know its potential sequestration. This paper aims to discern the potencyof carbon stocks in biomass of Long Ketrok protection forest managed bySetulang community, located in Malinau East Kalimantan. The method usedin this research is non-destructive using allometric equations developed intropical forests. Result of this study showed that carbon stored in biomass ofLong Ketrok protection forest is 304 ton/ha, consisting of C stored inaboveground biomass (255 ton/ha), root biomass (42 ton/ha), and necromass(7 ton/ha). The proportion of stem, branch, root, and leaf carbon biomass are:70.7%, 14.6%, 14.1% and 0.6% respectively.
biomass, carbon, protection forestKeywords:
UDC (OSDCF) 630*931Magdalena
The Roles of Customary Law in Forest Management and Protection in SesaotVillage, West Nusa Tenggara and Setulang Village, East Kalimantan
Forestry Socio Economic Journal Vol. 10 No. 2, p. 110 - 121
The challenges of forest management and protection In Indonesia often comefrom local community who live around the forest. However, some studies haveargued that customary practices of local community will support sustainableforest management. This research was to study 'how do local people and theircustomary law protect and manage their forest?' as well as to analyzedeterminant factors of customary law applied in forest management andprotection. The methods used were case study of two villages, that is, SesaotVillage, dominated by Sasak People (West Nusa Tenggara) and SetulangVillage, dominated by Dayak Kenyah People (East Kalimantan). Data wascollected through field observation and interviews with 30 government offials,20 NGO staff and 50 villagers. The study found that the existence ofcustomary forest was significant in protecting and sustaining forestmanagement. Factors that determined its sustainability were mainly cohesivity,kinship relationship, the present support of various stakeholders, clear propertyright as well as financial transparency and accountability.
forest management and protection, local community, customarylaws and factors
Keywords:
UDC (OSDCF) 630*116Edy Junaidi Retno Maryani
Effect of Spatial Dynamics of Socio-Economic in the Watershed LandscapeToward The Existence of the Forest Landscape; Case Studies on CitanduyHulu Watershed and Ciseel Watershed, West Java
Forestry Socio Economic Journal Vol. 10 No. 2, p. 122 - 139
Forest sustainability can not be separated from its surrounding environment,both ecological, economic and social. Management of forest resources that needto be done must be oriented toward ecosystem in totality. Therefore, thearrangement of land use forest plan need management at a landscape level. Thisstudy aims to investigate the interrelationship between socio-economic conditionsof the people residing at watershed and environmental conditions that affectdynamics of forest landscape. The method for determining closeness of eachcharacteristic (environmental and socio-economic) with the forest existence, usesGeographically Weighted Regression models (GWR), by looking at value ofthe correlation. Results showed that biophysical and socio-economic factors thathave a strong correlation toward existence of the forest landscape in theCitanduy Hulu Watershed and the watershed Ciseel were: (i) rainfall, (ii)slope, (iii) erosion soil sensitivity, (iv) drainage density, (v) average slope, (vi)density and (vii) dependence on agricultural land.
biophysical, social-economic and forest lansdcape
&
Keywords:
PERSAMAAN ALLOMETRIK BIOMASSA DAN KARBON UNTUKPENDUGAAN SIMPANAN KARBON DALAM MENDUKUNG UPAYA
KONSERVASI SAVANA CORYPHA UTANBiomass and Carbon Allometric Equation for Estimating Carbon
Stock to Support Corypha utan Savanna Conservation(
)
1 2
1,2
1,735 0,680
0,491
0,721 0,946
1,823
Dhany Yuniati, Hery KurniawanBalai Penelitian Kehutanan Kupang
Jln. Untung Suropati No. 7 (Belakang) P.O BOX 69 Kupang 85115 NTTTlp. (0380) 823357, Fax. (0380) 831068, email : [email protected]
iterima 15 Maret 2013, direvisi 10 April 2013, disetujui 22 Mei 2013
( ) ( )
( )( )
( )
Gewang ( ) merupakan jenis tanaman yang unik karena fungsinya sebagai sumber pangan,minuman, bahan bangunan (rumah, pagar, kandang) dan industri sederhana rumah tangga. Pemanfaatan olehmasyarakat dilakukan dengan penebangan pohon-pohon yang produktif sehingga mengancam kelestarian tanamangewang. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah sebaran alami yang potensial bagi pohon gewang.Di sisi lain tegakan gewang juga memiliki fungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sehingga keberadaantegakan dan proses permudaan perlu dijaga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan simpanan karbon hutansavana di NTT. Informasi mengenai kandungan karbon dalam gewang menjadi penting karena dengan informasitersebut dapat diketahui ukuran yang paling layak bagi gewang untuk ditebang dan dimanfaatkan. Sampai saat inibelum ada persamaan allometrik yang khusus dikembangkan untuk pendugaan potensi simpanan karbon padasavana gewang ( ). Penyediaan data dengan tingkat kerincian ( ) 3 memerlukan pendugaan cadangan karbonyang dimulai dari pendugaan biomassa dan karbon dengan menggunakan yang spesifik terhadap spesies dantempat ( ). Tulisan ini mengemukakan model persamaan allometrik untuk pendugaan biomassa pada tanamangewang ( ) dengan metode destruktif . Disamping itu dikemukakan pula model persamaan allometrikuntuk pendugaan simpanan karbon pada tanaman gewang ( ) dengan pengukuran langsung menggunakanmetode karbonasi atau pengarangan. Model persamaan allometrik untuk pendugaan biomasa batang tanamangewang ( ) y = 19703x , pendugaan biomasa daun y = 8449x dan pendugaan biomasa pelepah y =16855x . Hasil studi menghasilkan model persamaan allometrik untuk pendugaan karbon secara langsung padadaun tanaman gewang ( ) y = 10704x , pendugaan karbon secara langsung pada pelepah y = 15069x danpendugaan karbon secara langsung pada batang y = 27110x
Persamaan allometrik, biomassa, karbon, konservasi
D
.
Kata kunci:
ABSTRACT
Gewang is a unique species for its function as source of food, drink,construction material house, fence, shed andhome industry. People utilize it by cutting down the growing productive trees, causing the sustainability of gewang becomes threatened.Province of Nusa Tenggara Timur (NTT) is natural habitat for gewang distribution. On the other hand, stands have ability orfunction as carbon absorber and sinker also. Because of this, the existence and regeneration process should be guarded as this function is inline with the efforts to increase carbon stock of savanna forest in NTT. Information of carbon sink in trees became important,because of with this information could be understood the most feasible size/dimension of gewang to be harvested. Up to now there is noallometric equation which is specifically developed to estimate carbon stock potential on gewang's savanna . In order to providedata using of accuracy level 3 Tier 3 , carbon stock estimation was done by estimating biomass and carbon, modell for specific species andsite. This paper constructs allometric equation model for estimating gewang biomass with destructive sampling method. Inaddition, allometric equation for estimating carbon stock of gewang was constructed by direct estimation using carbonation method. The
study result in allometric equation model for estimating gewang stem biomass y = 19703x , for leaves biomass y = 8449x and for
midrib biomass y = 16855x . Allometric equation model to estimate carbon stock for gewang leaves y = 10704 x , for midrib y =
15069 x and for stem y = 27110 x
Allometric equations, biomass, carbon, , conservation
Corypha utan
C. utan Tiermodelling
siteC. utan sampling
C. utan
C. utan
C. utan
Corypha utan,
Corypha utan
C. utan
C. utan
C. utan
C. utan
1.735 0.680
0.491 0.721
0.946 1.823.
Keywords: Corypha utan
ABSTRAK
75Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk Pendugaan Simpanan Karbon dalam Mendukung ..... Dhany Yuniati, Hery Kurniawan( )
76JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 75 - 84
I. PENDAHULUAN
Gewang ( ) merupakan jenistumbuhan yang potensial bagi masyarakat NusaTenggara Timur (NTT). Fungsinya sangat strategisbaik sebagai sumber pangan, minuman, bahanbangunan (rumah, pagar, kandang) dan industrisederhana rumah tangga. Pemanfaatan gewang (
) oleh masyarakat lebih banyak dilakukandengan menebang tanaman yang masih produktif.Pohon gewang ( ) pada umur klimaks yangditandai dengan munculnya bunga akan mengalamikematian, sehingga perlu dilakukan pengaturan danpembatasan penebangan, mengingat pentingnyagewang bagi masyarakat NTT. Sebagai salah satutumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penyerapdan penyimpan karbon, maka kemampuannyadalam menyerap dan menyimpan karbon akanmenurun seiring dengan adanya pemanfaatan yangberlebih ditambah dengan adanya daur fisiologisgewang yang akan mengalami kematian sesaatsetelah berbuah.
Provinsi NTT merupakan sebaran alami yangpotensial bagi pohon gewang. Menurut Monk,(1997) paling sedikit ada delapan tipe savana diNusa Tenggara dan Maluku yang didasarkan padaspesies pohon yang dominan, dimana salah satunyaadalah tipe savana lontar ( ) dangewang ( ) Pulau-pulau di NTT yangmemiliki sebaran gewang yang luas dan signifikankeberadaanya adalah Pulau Timor, Sumba danFlores sedangkan pulau-pulau lainnya relatif kecil(Naiola, ., 2007). Keberadaan tegakan danproses permudaan harus dijaga dimana fungsi inijuga sejalan dengan upaya untuk meningkatkansimpanan karbon di hutan savana di NTT.
Dalam kaitannya dengan penyediaan datadengan tingkat kerincian ( ) 3 maka pendugaancadangan karbon dimulai dengan pendugaanbiomassa dan karbon menggunakan model yangspesifik terhadap spesies dan tempat (Wibowo,2009). Sampai saat ini belum ada persamaanallometrik yang khusus dikembangkan untukpendugaan potensi simpanan karbon pada savanagewang ( ). Berkaitan dengan penyediaan datadengan tingkat kerincian ( ) 3 dalam rangkamitigasi perubahan iklim maka perlu dibangunpersamaan allometrik khusus untuk gewang ( )untuk pendugaan potensi cadangan/simpanankarbon pada salah satu tipe savana yang ada di NTT.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun
Corypha utan
C.utan
C. utan
et al.
Borassus flabelliferC. utan .
et al
Tier
C. utanTier
C. utan
persamaan allometrik biomasa dan karbon gewang( ) untuk mendukung upaya konservasisavana gewang ( )
Pengambilan data dan bahan baku dilakukan diDesa Nekbaun Kecamatan Amarasi BaratKabupaten Kupang. Penelitian dilakukan padabulan April s/d September 2012. Analisis terhadapkandung an b iomassa d i l ak sanakan d iLaboratorium Balai Penelitian Kehutanan (BPK)Kupang. Analisis kandungan karbon dilakukan diLaboratorium Kimia Pusat Litbang KeteknikanKehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan(PUSTEKOLAH) Bogor dan LaboratoriumPadatan Balai Besar Teknologi KesehatanLingkungan dan Penyakit Menular (BBTKL)Jogjakarta. Analisis tanah dilakukan diLaboratorium Tanah Fakultas PertanianUniversitas Nusa Cendana (UNDANA). Analisislaboratorium dilaksanakan pada bulan Mei -November 2012.
Bahan yang digunakan adalah tegakan gewang( ) pada kelas tinggi 5-10 m, 11-15 m,16-20 m, 21-25 m dan 26-30 m dimana masing-masing kelas tinggi diambil tiga pohon sebagaisampel, peta pendukung dan data sekunder. Alatyang digunakan antara lain: GPS, phiband atau pitadiameter, hagameter, pita meter, gergaji rantai(c ), timbangan gantung dan duduk, cangkul,linggis, parang, gergaji tangan, patok kayu, talinilon, tali rapia, karung plastik, terpal, dan labelplastik.
Pengukuran biomassa batang, daun dan pelepahpada prinsipnya dilakukan dengan menimbangberat basah total setiap bagian secara terpisahdalam satu pohon untuk kemudian diambilsampelnya guna mengetahui berat keringnya.Pengambilan sampel batang dilakukan dalambentuk pada bagian pangkal tengah danujungnya Pengukuran berat kering untuk
C. utanC. utan
C. utan range
hainsaw
disc.
.
II. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
B. Bahan dan Alat Penelitian
C. Pengukuran Biomassa Batang, Daun danPelepah
77
menentukan kadar air dan menghitung biomassadilakukan dengan mengeringkan sampel yangdibawa dari lapangan dengan menggunakan ovenpada suhu 103 ± 2 C sampai didapatkan beratkonstan (Nelson ., 1999 dalam Losi, 2003).
Kandungan karbon tanaman dihitung berdasar-kan nilai karbon (C) pada setiap organ tanaman(batang, daun dan pelepah) kemudian dijumlahkanuntuk setiap pohon. Pengukuran kandungankarbon pada organ tanaman dilakukan secaralangsung yakni dengan menggunakan metodekarbonisasi atau pengarangan. Komponen pohonyang terdiri atas batang, cabang, ranting/daun danbuah yang telah dilakukan pengukuran berat kering,diambil sampel dengan berat tertentu untukdilakukan proses pengarangan atau karbonasidengan menggunakan retort listrik pada suhu akhir500 C selama ± 4 jam. Selama proses pengarangan,produk gas yang dihasilkan dialirkan dalam pipakaca dan diberi perlakuan pendinginan dengan airyang mengalir, sehingga dihasilkan cairankondensat yang disebut distilat. Hasil distilat iniselanjutnya ditampung dengan labu kaca, untukdiukur rendemen dan kadar karbonnya, pada suhuakhir 500 C proses dihentikan. Sisa pembakaranberupa arang, dikeluarkan dan ditimbang beratnyauntuk mengetahui rendemen arang dari bahanbaku. Terhadap produk dari proses karbonasi yangberupa distilat dan arang selanjutnya dilakukanpengujian untuk mengetahui kadar karbon darimasing-masing produk.
Perhitungan dan analisis statistik dilakukandengan menggunakan bantuan program komputer.Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapamodel persamaan yang diduga kuat sesuai dengansebaran data yang diperoleh. Penyusunanpersamaan allometrik biomassa dan karbon tegakangewang ( ) dilakukan melalui 7 (tujuh) per-samaan yang diduga kuat sesuai dengan bentuksebaran data yang ada, yakni persamaan model
,dan . Variabel bebas dan model
persamaan yang diajukan kemudian dipilih sebagaimodel persamaan allometrik dengan kriteria
0
0
0
et al
C. utan
logarithmic power, growth, quadratic, exponential, logistic,quadratic linear
D. Pengukuran Karbon Batang, Daun danPelepah
E. Analisis Data
memiliki nilai koefisien determinasi tertinggi dannilai sisaan atau ( )yang paling kecil (Walpole, 1993). Seluruh per-hitungan menggunakan satuan sentimeter (cm)untuk diameter setinggi dada (dbh), meter (m)untuk tinggi dan kilogram (kg) untuk berat bio-massa. Bentuk persamaannya secara matematisadalah sebagai berikut :
= a log x
= ax
= ab
= ae
=
= ax + bx - c
= ax + b
Hasil analisis pada penyusunan persamaanallometrik untuk pendugaan biomassa pada jenisgewang, baik pada daun, pelepah maupun batangyang digunakan sebagai variabel pembuka adalahtinggi total. Pada Gambar 1 disajikan persentasebiomassa rata-rata pohon gewang ( )berdasarkan komponen pohon.
Tinggi total merupakan representasi daripanjang batang. Komposisi biomassa padakomponen pohon gewang ( ) berbeda-bedadan terbesar dalam batang, pelepah dan terakhirdaun (Yuniati , 2012), sehingga ketika tinggitotal merupakan variabel pembuka dalam allometriktanaman gewang hal tersebut sangat dimungkin-kan. Gewang juga merupakan tumbuhan mono-kotil sehingga banyak mengalami pertumbuhanprimer (ke atas) dari pada sekunder (ke samping)sehingga tinggi total akan lebih berpengaruh kevolume pohon yang selanjutnya akan berpengaruhke biomassanya.
Berdasarkan gambaran sebaran data yang ada,diajukan lima model persamaan yakni
Standard Error of Estimation SEE
Logarithmic
Power
Growth
Exponential
Logistic
Quadratic
Linear
C. utan
C. utan
, et al.
logarithmic,
b
b
x
bx
2
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyusunan Persamaan Allometrik untukPendugaan Biomassa Pada Jenis Gewang( )
1. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan biomassa daun tanamanGewang ( )
Corypha utan
Corypha utan
Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk Pendugaan Simpanan Karbon dalam Mendukung ..... Dhany Yuniati, Hery Kurniawan( )
78
95%
3% 2%
Biomasa (ton)
Batang Pelepah Daun
Gambar 1. Rata-rata persentase biomassa pohon gewang ( ) berdasarkankomponen pohon
C.utan
Figure 1. Biomass percentage mean of gewang tree based on tree component
Tabel 1. Hasil analisis regresi pada pendugaan biomassa daunTable 1. Result of regression analyses on leaf biomass
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)R kuadrat
(R Square)F df1 df2 Sig
Konstan(Constant)
b1 b2
Logarithmic 0,565 13,007 1 - 0,005 2353,396 17757,633 - 10641,136
Power 0,600 15,006 1 - 0,003 8448,824 0,680 - 0,380
Growth 0,436 7,723 1 - 0,019 9,738 0,027 - 0,451
Exponential 0,436 7,723 1 - 0,019 16955,008 0,076 - 0,451
Logistic 0,436 7,723 1 - 0,019 5,898E-5 0,927 - 0,451
Keterangan ( ) :Variabel bebas ( ) : tinggi total ( )Variabel terikat ( ) : biomassa ( )
Remarkindependent variable total heightdependent variable biomass
y = 8448.821x 0.681
R² = 0.600
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0 5 10 15 20
Tinggi Total
Biomassa
Power (Biomassa)
Bio
mas
saD
aun
Gambar 2. Sebaran data dan persamaan model pada pendugaan biomassa daunpower
Figure Data distribution and power equation for leaf biomass2.
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 75 - 84
79
power, growth, exponential logisticdan menggunakanvariabel bebas tinggi total. Hasil analisis regresidisajikan pada Tabel 1.
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikanpada Tabel 1 dan kriteria yang ada maka dipilihmodel persamaan sebagai model persamaanallometrik untuk pendugaan biomassa dauntanaman gewang.
Dalam gambar 2 disajikan sebaran data, gariskecenderungan dan persamaan allometrik untukpendugaan biomassa daun tanaman gewang.
Hasil analisis regresi menunjukkan nilaikonstanta sebesar 8448,824 dan koefisien per-samaan adalah 0,680. Dengan demikian bentukpersamaan regresinya adalah Y = 8449x . Nilaisignifikansi 0,003 menunjukkan bahwa koefisienkorelasi yang dihasilkan adalah signifikan secarastatistik. Koefisien determinasi yang diperolehadalah 0,600 ini menunjukkan bahwa sekitar 60%varian dari sebaran data dapat dijelaskan olehpersamaan tersebut.
power
slope
0.680
2. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan biomassa pelepah tanamanGewang ( )Corypha utanBerdasarkan gambaran sebaran data yang ada,
diajukan lima model persamaan yakni, dan . Hasil analisis
regresi disajikan pada Tabel 2.Seperti halnya pada persamaan allometrik untuk
pendugaan biomassa daun, persamaan allometrikuntuk pendugaan biomassa pelepah berdasarkankriteria yang ada maka dipilih persamaan model
sebagai model persamaan allometrik untukpendugaan biomassa pelepah.
Dalam gambar 3 disajikan model persamaandan sebaran data yang dihasilkan untuk pendugaanbiomassa pelepah tanaman gewang. Nilai koefisiendeterminasi yang dihasilkan adalah 0,569 artinya56,9% varian dari sebaran data dapat dijelaskanoleh persamaan tersebut. Nilai ini tidak setinggipada biomassa daun namun secara statistik dapatdigunakan dalam pendugaan karena nilai
logarithmic,quadratic power, exponential logistic
power
Tabel 2. Hasil analisis regresi untuk pendugaan biomassa pelepahTable 2. Result of regression analyses on midrib biomass
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)R kuadrat
(R Square)F df1 df2 Sig
Konstan(Constant)
b1 b2
Logarithmic 0,472 6,259 1 - 0,041 9901,594 20264,36 - 17422,795Quadratic 0,515 3,187 2 - 0,114 4917,294 9186,514 -339,144 18035,306Power 0,569 9,258 1 - 0,019 16854,642 0,491 - 0,347Exponential 0,438 5,456 1 - 0,052 27038,22 0,055 - 0,397Logistic 0,438 5,456 1 - 000 3,698E-5 0,946 - 0.397
y = 16855x 0.491
R² = 0.569
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
70000.00
80000.0090000.00
0 10 20
Tinggi Total
Biomassa
Power(Biomassa)
Bio
mas
saP
elep
ah
Gambar 3. Sebaran data dan persamaan model r pada pendugaan biomassa pelepah3.
poweFigure Data distribution and power equation for midrib biomass
Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk Pendugaan Simpanan Karbon dalam Mendukung ..... Dhany Yuniati, Hery Kurniawan( )
80
signifikansinya sebesar 0,019. Dengan demikiandipilih persamaan model y = 16855x ,sebagai persamaan untuk pendugaan biomassapelepah pohon gewang ( ).
Guna penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan biomassa batang tanaman gewangdiajukan lima persamaan dalam analisis regresi,yakni model
. Terlihat bahwa model regresi terbaik adalahmodel persamaan dengan nilai koefisiendeterminasi tertinggi yakni 0,850 dan terendahyakni 0,482. Tabel 3 menampilkan hasil analisis
power
C. utan
quadratic, power, growth, exponential danlogistic
powerSEE
0,491
3. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan biomassa batang tanamanGewang ( )Corypha utan
regresi untuk pendugaan biomassa batang tanamangewang.
Gambar 4 disajikan persamaan model dansebaran data yang dihasilkan pada persamaanallometrik untuk pendugaan biomassa batangtanaman gewang. Nilai konstantanya adalah 19703,dan nilai koefisien persamaan adalah 1,735.
Nilai signifikansi sebesar 0,00 menunjukkanbahwa koefisien korelasi yang dihasilkan adalahsangat signifikan. Nilai koefisien determinasi yangdihasilkan adalah 0,850 artinya 85% varian darisebaran data dapat dijelaskan oleh persamaantersebut. Dengan demikian dapat dipilihpersamaan model y = 19703x , sebagaipersamaan untuk pendugaan biomassa batangtanaman gewang.
power
slope
power1,735
Tabel 3. Hasil analisis regresi pada pendugaan biomassa batangTable 3. Result of regression analysis on stem biomass
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)R kuadrat
(R Square)F df1 df2 Sig
Konstan(Constant)
b1 b2
Quadratic 0,746 17,663 2 - 0,33 -882156,478 309439,789 -7455,16 521962,973
Power 0,850 74,193 1 - 0,00 19702,856 1,735 - 0,482
Growth 0,722 33,770 1 - 0,00 11,628 0,197 - 0,658
Exponential 0,722 33,770 1 - 0,00 112231,483 0,197 - 0,658
Logistic 0,722 33,770 1 - 0,00 8,910E-6 0,821 - 0.658Keterangan ( ) :Variabel bebas ( ) : tinggi total ( )Variabel terikat ( ) : biomassa ( )
Remarkindependent variable total heightdependent variable biomass
y = 19703x1.735
R² = 0.850
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
0 5 10 15 20Tinggi Total
Biomassa
Power (Biomassa)Bio
mas
saB
atan
g
Gambar 4. Sebaran data dan persamaan model power pada pendugaan biomassa batangFigure 4. sData distribution and power equation for stem biomas
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 75 - 84
81
B. Penyusunan Persamaan Allometrik untukPendugaan Simpanan Karbon padaTanaman Gewang ( )Corypha utan
Hasil analisis pada penyusunan persamaanallometrik untuk pendugaan karbon secara langsungpada jenis gewang, baik pada daun, pelepah maupunbatang yang digunakan sebagai variabel pembukaadalah tinggi total. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tinggi total yang merupakan gambarandari panjang batang dimana komponen biomassaterbesar terdapat pada batang, sedangkan simpanankarbon dapat didekati dengan pendugaan besarnyabiomassa karena karbohidrat hasil fotosintesisdisimpan dalam organ tanaman hidup (biomassa).Berdasarkan pada gambaran sebaran data yang ada,diajukan lima model persamaan yakni ,
dan .linear
logarithmic, quadratic, power growth
1. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan karbon daun tanaman Gewang( )Corypha utanHasil analisis regresi disajikan pada Tabel 4.Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan
pada Tabel 4 diketahui bahwa persamaan yangmemiliki koefisien determinasi (R ) tertinggi danmemiliki yang kecil adalah persamaan model
, sehingga dipilih persamaan model ini sebagaimodel persamaan allometrik untuk pendugaankarbon pada daun tanaman gewang.
Pada Gambar 5 disajikan sebaran data, gariskecenderungan dan persamaan allometrik untukpendugaan karbon pada daun tanaman gewang.
Hasil analisis regresi menunjukkan nilaikonstanta sebesar 10704 dan koefisienpersamaan adalah 0,721, dengan demikian bentuk
2
SEEpower
slope
Tabel 4. Hasil analisis regresi pada pendugaan karbon daunTable 4. Result of regression analyses on leaf carbon
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)R kuadrat
(R Square)F df1 df2 Sig
Konstan(Constant)
b1 b2
Linear 0,635 17,397 1 - 0,002 18932,486 3736,106 - 14725,410
Logarithmic 0,654 18,922 1 - 0,001 -5706,627 28847,114 - 14332,071
Quadratic 0,641 8,018 2 - 0,010 12766,444 5428,559 -87,907 15404,341
Power 0,693 22,567 1 - 0,001 10704,333 0,721 - 0,328
Growth 0,592 14,489 1 - 0,003 9,951 0,088 - 0,378
Keterangan ( ) :Variabel bebas ( ) : tinggi total ( )Variabel terikat ( ) : karbon ( )
Remarkindependent variable total heightdependent variable carbon
y = 10704x 0,721
R² = 0,69 3
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
0 5 10 15 20
Tinggi Total
C. Rerata
Power (C. Rerata)
Gambar 5. Sebaran data dan persamaan model pada pendugaan karbon daunpowerFigure 5. Data distribution and power equation for leaf carbon
Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk Pendugaan Simpanan Karbon dalam Mendukung ..... Dhany Yuniati, Hery Kurniawan( )
82
persamaan regresinya adalah Y = 10704x . Nilaisignifikansi 0,001 menunjukkan bahwa koefisienkorelasi yang dihasilkan adalah signifikan secarastatistik. Koefisien determinasi yang diperolehadalah 0,693 ini menunjukkan bahwa sekitar 69,3%varian dari sebaran data dapat dijelaskan olehpersamaan tersebut.
Berdasarkan analisis regresi sebagaimanadisajikan pada Tabel 5, diketahui nilai koefisiendeterminasi (R ) tertinggi dengan yang kecildihasilkan oleh persamaan , sehingga dipilih
0,721
2
2. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan karbon pelepah tanaman Gewang( )Corypha utan
SEEpower
persamaan model sebagai model persamaanallometrik untuk pendugaan karbon pelepahtanaman gewang.
Dalam gambar 6 disajikan model persamaandan sebaran data yang dihasilkan untuk pendugaankarbon pada pelepah tanaman gewang. Nilaikoefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,663artinya 66,3% varian dari sebaran data dapatdijelaskan oleh persamaan tersebut. Nilaisignifikansinya sebesar 0,022 menunjukkan bahwakoefisien korelasi yang dihasilkan adalah signifikansecara statistik. Dengan demikian dapat dipilihpersamaan model y = 15069x , sebagaipersamaan untuk pendugaan karbon pelepahtanaman gewang ( ).
power
power
C. utan
0,946
Tabel 5. Hasil analisis regresi untuk pendugaan karbon pelepahTable 5. Result of regression analyses on midrib carbon
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)R kuadrat
(R Square)F df1 df2 Sig
Konstan(Constant)
b1 b2
Linear 0,468 7,917 1 - 0,020 -13947,582 16423,864 - 100754,883
Logarithmic 0,383 5,594 1 - 0,042 -103672,189 118889,246 - 108477,279
Quadratic 0,518 4,306 2 - 0,054 78939,925 -7582,056 1152,313 101673,837
Power 0,663 17,672 1 - 0,022 15068,773 0,946 - 0,486
Growth 0,577 12,286 1 - 0.007 10,528 0,110 - 0,544Keterangan ( ) :Variabel bebas ( ) : tinggi total ( )
Remarkindependent variable total height
Variabel terikat ( ) : karbon ( )dependent variable carbon
y = 15069x 0,946
R² = 0,663
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
0 5 10 15 20
Tinggi Total
C total
Power (C total)
Car
bon
Pel
epah
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 75 - 84
Gambar 6. Sebaran data dan persamaan model r yang dihasilkan pada pendugaan karbonpelepah
powe
Figure 6. Data distribution and power equation for midrib carbon
83
3. Penyusunan persamaan allometrik untukpendugaan karbon batang tanamanGewang ( )Corypha utanTabel 6 menampilkan hasil analisis regresi untuk
pendugaan karbon batang tanaman gewang.Berdasarkan analisis regresi sebagaimana
disajikan pada Tabel 6 diketahui, nilai koefisiendeterminasi (R ) tertinggi dengan yang kecildihasilkan oleh persamaan , sehingga dipilihpersamaan model sebagai model persamaanallometrik untuk pendugaan karbon batangtanaman gewang.
Pada Gambar 7 disajikan persamaan modeldan sebaran data yang dihasilkan pada persamaanallometrik untuk pendugaan karbon pada batangtanaman gewang.
2SEE
powerpower
power
Nilai konstantanya adalah 27110, dan nilaikoefisien persamaan adalah 1,823. Nilaisignifikansi yang jauh lebih kecil dari 0,00menunjukkan bahwa koefisien korelasi yangdihasilkan adalah sangat signifikan. Nilai koefisiendeterminasi yang dihasilkan adalah 0,881 artinya88,1% varian dari sebaran data dapat dijelaskanoleh persamaan tersebut. Dengan demikian dapatdipilih model persamaan y = 27110x ,sebagai persamaan untuk pendugaan karbon padabatang tanaman gewang ( ).
Berdasarkan hasil penelitian, gewang ( )secara alami mampu mencapai tinggi pohon antara15-20 meter. Untuk mendapatkan gewang
slope
power
C. utan
C. utan
(C. utan)
1,823
4. Implikasi teknis terhadap umur pemanfaat-an Gewang (C. utan)
Tabel 6. Hasil analisis regresi pada pendugaan karbon batangTable 6. Result of regression analyses on stem carbon
Persamaan(Equation)
Ringkasan model(Model summary)
Parameter dugaan(Parameter estimates) Nilai sisaan
(Std.error ofestimate)
R kuadrat(R Square)
F df1 df2 Sig.Konstanta(Constanta)
b1 b2
Linear 0,825 56,477 1 - 0,000 -780417,668 291300,769 - 668666,675
Logarithmic 0,732 32,847 1 - 0,000 -2,419e6 2,100e6 - 826255,209Quadratic 0,830 26,760 2 - 0,000 -384174,048 183134,139 5661,796 688861,806
Power 0,881 89,129 1 - 0,000 27110 1,823 - 0,435Growth 0,786 43,992 1 - 0,000 11,895 0,225 - 0,585Keterangan ( ) :Variabel bebas ( ) : tinggi total ( )Variabel terikat ( ) : karbon ( )
Remarkindependent variable total heightdependent variable carbon
y = 27110x 1,823
R² = 0,881
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
0 5 10 15 20
Tinggi Total
C total
Power (C total)
Kar
bon
Bat
ang
Persamaan Allometrik Biomassa dan Karbon untuk Pendugaan Simpanan Karbon dalam Mendukung ..... Dhany Yuniati, Hery Kurniawan( )
Gambar 7. Sebaran data dan persamaan model power yang dihasilkan pada pendugaankarbon batang
Figure 7. Data distribution and power equation for stem carbon
84
dengan tinggi diatas 20 meter sangat sulit dijumpai.Pada saat mencapai tinggi maksimal inilah gewang( ) juga akan mengalami pematangan secarabiologis kemudian berbuah dan mati perlahansecara alami.
Apabila dikaitkan dengan aspek konservasimaka sesungguhnya gewang ( ) akan stagnandalam kemampuannya menimbun karbon pada saatmencapai tinggi maksimal tersebut. Berdasarkaninformasi dari masyarakat setempat umur yangdiperlukan untuk mencapai tinggi maksimaltersebut adalah antara 30-40 tahun. Sehingga,pemanfaatan gewang ( ) oleh masyarakatsemestinya memperhatikan daur biologis ini.Namun, untuk gewang ( ) yang terlalu tua danmatang berbuah, diketahui kandungan putaksebagai pakan ternak juga sudah hilang. Sehinggauntuk kebutuhan pakan ternak dapat dilakukanbeberapa tahun sebelum gewang mencapai umurmatang biologis. Hanya saja pemanfaatan untukpakan ternak ini perlu diatur lebih lanjut, mengingatperlu disediakan pohon yang cukup untuk berbuahdan menggugurkan buahnya, serta mati secara alamidan proses regenerasi secara alami dapatberlangsung secara berkelanjutan.
Model persamaan allometrik untuk pendugaanbiomassa batang tanaman gewang ( ) y =19703x , pendugaan biomassa daun y =8449x dan pendugaan biomassa pelepah y =16855x .Model persamaan allometrik untuk pendugaankarbon secara langsung pada daun tanamangewang ( ) y = 10704x , pendugaankarbon secara langsung pada pelepah y =15069x dan pendugaan karbon secaralangsung pada batang y = 27110x .Secara alami gewang ( ) mampu mencapaitinggi 15-20 meter dan mengalami kematanganfisiologis setelah itu. Pemanfaatan gewang (
) semestinya memperhatikan daur fisiologisgewang ( ), dengan menetapkan pohon-pohon tertentu untuk dibiarkan mencapai umurmaksimal sebagai sumber permudaan.Dalam kaitannya dengan kandungan karbon,berdasarkan grafik kandungan karbon pada
C. utan
C. utan
C. utan
C. utan
C. utan
C. utan
C. utan
C.utan
C. utan
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
KesimpulanA.
1.
2.
3.
4.
1,735
0,680
0,491
0,721
0,946
1,823
batang diketahui sesungguhnya gewang () masih memiliki kemampuan menyerap
dan menyimpan karbon hingga tinggimaksimalnya atau mendekati umur matangbiologisnya.
Penebangan dalam jumlah besar gewang diwilayah NTT hendaknya dihindari untuk alasankepentingan lingkungan.Untuk pendugaan biomassa batang, daun danpelepah tanaman gewang ( ) dapatdigunakan model persamaan yang dihasilkandari penelitian ini.Untuk kepentingan pendugaan cadangankarbon dapat disusun model persamaanallometrik dengan proses dan metode yangsama, dengan asumsi seluruh prosespengarangan, karbonasi dan destilasi besertaanalisisnya berjalan dengan normal dan wajar.
Losi, C.J., Thomas, G.S., Richard, C., Juan, E.M. 2003.Analysisof AlternativeMethodsforEstimatingCarbon Stock in Young Tropical Plantations,ForestEcologyandManagement184,355-368.
Monk, K.A., Y., de Fretes, Gayatri, R., Lilley. 1997.The Ecology of Nusa Tenggara dan Maluku.The Ecology of Indonesia Series. Vol V. 187 -299.
Naiola, B. Paul, Johanis P. Mogea, Subyakto. 2007.Gewang: Biologi, Manfaat, Permasalahan danPeluang Domestifikasi. Lembaga Ilmu Pe-ngetahuanIndonesia (LIPI).LIPIPress.Bogor.
Walpole, E.R. 1993. Pengantar Statistika (ed ke-3).Gramedia. Jakarta.
Wibowo, A. 2009. RPI Pengembangan Perhitung-an Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan. PusatPenelitian Sosial Ekonomi dan KebijakanKehutanan. Bogor.
Yuniati, D., Hery, K. 2012. Penyusunan PersamaanAllometrik Borassus flabelifer dan Coryphautan Untuk Pendugaan Simpanan KarbonHutan Savana di Provinsi Nusa TenggaraTimur. Laporan Hasil Penelitian (Tidak Di-publikasikan).
C.utan
C. utan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 75 - 84
ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASIKEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)(
)Learning Organization and Policy Implementation of
Community Forest
Hariyatno Dwiprabowo , Mulyaningrum , Eno SuwarnoPusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunungbatu 5, PO Box 272, Telp. 8633944, Bogor.email: [email protected]
Prodi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB , BandungFakultas Kehutanan, Universitas Lancang Kuning
Jl. DI Panjaitan Km 8,5 Rumbai, Pekanbaru, Telp. (0761) 7078907
iterima 1 Maret 2013, direvisi 12 April 2013, disetujui 16 Mei 2013
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangankapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian inibertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar ( ), organisasi pelaksana yang terlibatprogram Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dankuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukandengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di ProvinsiSulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi ataumasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar:
telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yangmenjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritislain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnyaterjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkmmasih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.
Kata kunci:
1 2 3
1
2
3
D
ABSTRACT
The undertaking of community forest (Hkm) program by government is aimed at capacity development and access granting oflocal people in managing forest sustainably. The study aims to assess, through characteristics of learning organization, the governmentexecuting institutions involving in Hkm program and Hkm policy implementation. Research method used was qualitative method byusing observation, in-depth interview, document reading, and scoring method. Method of analysis was discourse, actors or network andtheir interests following policy process approach. Study took place in South Sulawesi, Lampung and Nusa Tenggara Barat provinces.Research respondents were individual, group, agencies, and community. Results showed that fulfilment of learning organizationcharacteristics : system thinking, personal mastery, mental models, shared vision, team learning, has been achieved at different degrees insampled agencies. Leadership in certain agency becomes crucial in order learning organization to be well realized. Other critical factor inlearning organization realization is shared vision in which in general agencies have difficulty in interpreting and implementingorganization vision and mission. Hkm policy are still facing weakness in its implementation by executing agencies and communityinvolved.
Keywords: Community forest, learning organization, policy process
Learning Organization
scoring
system thinking,personal mastery, mental models, shared vision, team learning,
shared vision,
ABSTRAK
Hutan kemasyarakatan (Hkm), organisasi belajar,proses kebijakan
85Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
I. PENDAHULUAN
Pemerintahan pada hakikatnya merupakanproses untuk melaksanakan fungsi-fungsi peng-aturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan
dengan optimal. Di dalam prakteknya, pelaksanaanfungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasipemerintahan. Dalam konsep birokrasi idealseperti dikemukakan Max Weber, birokrasimerupakan organisasi yang melaksanakan
86JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristikhirarkis, memiliki rantai komando, terdapatpembagian dan diferensiasi pekerjaan. Sebagaisuatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlahstruktur yang menjalankan fungsi dan pembagiankerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahamanorganisasi dalam perspektif statis maupun dinamis.Dalam perspektif statis, organisasi mewujudsebagai suatu lembaga atau wadah. Sementaradalam perspektif dinamis, organisasi mengandungaspek ketatalaksanaan dalam proses dinamikaorganisasi. Pada prinsipnya, struktur organisasi dantata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensidari bentuk organisasi birokrasi diterapkan denganberlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apaserta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalamorganisasi pemerintahan dikenal adanya strukturorganisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsilini, dan fungsi teknis (Dwiyanto, 2011).
Pengurusan dan pengelolaan hutan secaraumum dalam prakteknya di lapangan sangatditentukan oleh keragaan kebijakan pemerintah danefektivitas implementasinya di lapangan.Penurunan kinerja pembangunan kehutanan yangtelah terjadi, membuktikan bahwa implementasikebijakan tersebut belum efektif. Efektivitasimplementasi suatu kebijakan dapat terjadi hanyaapabila kebijakan dirumuskan atas dasar penetapanmasalah yang tepat serta terdapat kemampuan dankapasitas menjalankan solusinya di lapangan(Dunn, 1994). Apabila pandangan ini diikuti, makafenomena penurunan kinerja pembangunankehutanan merefleksikan hadirnya masalah-masalah pokok, terutama belum tepatnyapenetapan dan pendefinisian masalah dalam prosesperumusan kebijakan selama ini.
Selama ini kebijakan secara intrinsik dianggapsebagai urusan teknis dan rasional, yaitu sebagai alatpemerintah untuk memecahkan masalah danmengubah keadaan. Pandangan umum bahwakebijakan sebagai prinsip-prinsip yang menentukantindakan langsung masyarakat ke arah tujuan akhirtertentu yang telah ditetapkan, ternyata padaumumnya di sektor kehutanan tidak memenuhiasumsi dasarnya. Oleh karena itu perlu dilakukanpengkajian terhadap gabungan problematika teknisdengan problematika organisasi di sektorkehutanan.
Sejak tahun 1995 Kementerian Kehutanan telahmengeluarkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan(HKm) melalui Keputusan Menteri Kehutanan
No.622/Kpts-II/1995. Kemudian diganti melaluiSurat Keputusan Menteri Kehutanan dan Per-kebunan No.677/Kpts-II/1998 Jo No.865/Kpts-II/1999. Setelah itu terjadi perubahan lagi melaluiSurat Keputusan Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2001. Dan terakhir melalui Peraturan MenteriKehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 Jo P.18/Menhut-II/2009 Jo P.13/Menhut-II/2010 JoP.52/Menhut-II/2011 Penyelenggaraan HKm( ) dimaksudkan untuk pe-ngembangan kapasitas dan pemberian akseskepada masyarakat setempat dalam mengelolahutan secara lestari guna menjamin ketersediaanlapangan kerja bagi masyarakat setempat untukmemecahkan persoalan ekonomi dan sosial yangterjadi di masyarakat.
Luas izin usaha pemanfaatan HKm secaranasional baru mencapai 46.435 ha (25%) dari yangsudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan seluas186.931 ha (Himawan, 2012 dalam Anonim, 2012).Mengacu kepada awal tahun dikeluarkannyakebijakan HKm yaitu pada tahun 1995, berartisampai saat ini telah berusia 17 tahun namunpencapaian program masih rendah. Perjalananpanjang riwayat kebijakan HKm di Indonesia,dapat menjadi obyek kajian yang menarik untukmengetahui sejauh mana pengalaman perumusandan implementasi kebijakan ini dapat dijadikansebagai pembelajaran oleh berbagai pemangkukepentingan, khususnya pihak pemerintah, dalamupaya meningkatkan kinerja organisasinya.
Permasalahan HKm dalam tulisan ini dikajiberdasarkan organisasi belajar ( -
), yaitu organisasi dimana para anggotanya terusmenerus meningkatkan kapasitasnya untuk meraihhasil yang benar-benar diinginkannya, dimana polapikir baru dipupuk dan dikembangkan, dimanaaspirasi kolektif diberi ruang kebebasan, dandimana para anggotanya terus-menerus belajaruntuk belajar semua hal bersama-sama” (Senge,1990). Maknanya adalah Kementerian Kehutananmaupun Dinas Kehutanan Kabupaten yangmerupakan organisasi secara fisik telah men-jalankan proses organisasi belajar sebagai disiplininti yang mengakumulasikan pengetahuan dansikap pembelajaran. Tentunya hal ini berbedadengan pemahaman yang mengandungmakna gambaran dari penerapan aturan main (
) dalam suatu tatanan kehidupan sosial (Scott,2008). HKm sebagai sebuah produk kebijakan, didalam pemecahan permasalahannya selain dikaji
community forest
Learning Organization
institutionrule
in use
87
dari unsur kelembagaan sosial, perlu dikaji pulamelalui proses pembuatan kebijakannya dengandasar kesepahaman pembuatan kebijakan (IDS,2006).
Tujuan penelitian ini adalah menganalisisorganisasi dan kebijakan terkait dengan programHKm di Kementerian Kehutanan dan instansi lainyang terkait dengan HKm. Hasil kajian diarahkanuntuk memberikan rekomendasi perbaikankelembagaan yang dapat meningkatkan kinerjapenyelenggaraan Hkm
Organisasi belajar ( ) adalahsuatu konsep dimana organisasi terus menerusmelakukan proses pembelajaran mandiri (
) sehingga organisasi tersebut memiliki'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam meresponberagam perubahan yang muncul.
Secara akademik, pengertian organisasi belajaradalah proses belajar pada tingkat individu,kelompok dan organisasi dengan cara kerja yangsimultan.
Organisasi belajar memiliki lima karakteristikutama yang dikenal dengan lima disiplin yangdiharapkan dapat mewujudkan organisasi bisnismenjadi organisasi yang inovatif (Senge, 1990),yaitu :
Organisasi pada dasarnya terdiri atas unit yangharus bekerja sama untuk menghasilkan kinerjayang optimal. Unit-unit itu antara lain berupa divisi,direktorat, bagian, atau cabang. Kesuksesan suatuorganisasi sangat ditentukan oleh kemampuanorganisasi untuk melakukan pekerjaan secarasinergis. Kemampuan untuk membangunhubungan yang sinergis ini hanya akan dimilikikalau semua anggota unit saling memahamipekerjaan unit lain dan memahami juga dampak darikinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya.Akumulasi pengetahuan dari pembelajaran setiapindividu yang kemudian dibagi kepada anggotaorganisasi lainnya sehingga menjadi pengetahuantim.
.
II. METODE PENELITIAN
A. Kerangka Teoritis dan PendekatanPenelitian
Learning Organization
selflearning
a. System Thinking
b. Personal Mastery
c. Mental Model
d. Shared Vision
e. Team Learning
Mendorong organisasi untuk terus menerusbelajar bagaimana cara untuk menciptakan masadepan yang hanya bisa terwujud bila individu-individu para anggota organisasi mau dan mampuuntuk terus belajar dan membuat dirinyamenguasai bidang ilmunya. Berkembangnyaberbagai keterampilan individu para anggotaorganisasi melakukan refleksi diri; untuk menemukenali kekuatan dan kelemahan kompetensiintelektual, emosional maupun sosial dirinya;untuk melakukan revisi atas visi pribadinya, danuntuk membangun kondisi kerja yang sesuaidengan kondisi organisasi. Disamping itu, keahlianindividu plus komitmen tinggi berkembang dalamproses pembelajaran dirinya sendiri.
Proses mental yang harus dimiliki bersama olehseluruh anggota organisasi dengan belajar nilai-nilai yang sejalan dengan kebutuhan danperkembangan organisasi dan membuang nilai-nilai yang tidak relevan serta menghambat. Denganmelalui pengembangan mental model makadimungkinkan manusia bekerja dengan lebihcepat.
Visi bersama ini menjadi arahan dan sekaligusmemicu semangat dan komitmen untuk selalubelajar bersama. Dibutuhkan kemampuan untukmenyesuaikan antara visi pribadi dengan visiorganisasi. Visi ini bukanlah sesuatu yangdipaksakan oleh pimpinan organisasi, tetapidibangun berdasarkan komitmen diri untukmenggali visi bersama tentang masa depan secaramurni. Dalam organisasi yang terdiri atas berbagaiorang yang berbeda latar belakang pendidikan,kesukuan, pengalaman serta budayanya, makatanpa visi yang sama akan sangat sulit bagiorganisasi untuk bekerja secara terpadu.
Kemampuan dan motivasi untuk belajar secaraadaptif, generatif, dan berkesinambungan.Kemampuan organisasi untuk mensinergikankegiatan tim ini ditentukan oleh adanya visibersama dan kemampuan berfikir sistemik sepertiyang telah diuraikan di atas. Namun demikiantanpa adanya kebiasaan berbagi wawasan ataskeberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalamsuatu tim, maka pembelajaran organisasi akan
Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
88
lambat dan bahkan berhenti. Pembelajaran dalamorganisasi akan semakin cepat kalau individu mauberbagi wawasan bersama-sama. Berbagi wawasanpengetahuan dalam tim menjadi sangat pentinguntuk peningkatan kapasitas organisasi dalammenambah modal intelektualnya.
Kondisi yang dibutuhkan dalam organisasibelajar harus dilihat atau dipandang secara holistik(Senge, 1996), yaitu :1. Seluruh individu di dalam organisasi harus
bekerja sama dengan individu yang lain secaralintas organisasi,
2. dan bertujuan memecahkan persoalan danmenciptakan solusi yang inovatif.Organisasi seperti kegiatan menenun kain secara
berkesinambungan memperbesar kapasitas untukbelajar, beradaptasi dan mengubah budaya dengannilai-nilai, kebijakan-kebijakan, praktek-praktek,sistem dan struktur yang dapat mendukung danmeningkatkan pembelajaran bagi seluruh karyawan.Organisasi secara berkesinambungan meningkatdengan cepat da lam menciptakan danmenyempurnakan kapabilitas yang diperlukanuntuk masa depan. Para ahli organisasi belajarmengatakan bahwa efektivitas kinerja organisasidapat ditingkatkan dengan cara mengadopsi fitur-fitur yang diuraikan sebagai komponenpembelajaran (Senge, 1996).
Berhasil tidaknya kebijakan HKm akan sangatdipengaruhi oleh pelaksanaan peran masing-
masing pemangku kepentingan. Secara teoritispelaksanaan peran masing-masing pemangkukepentingan juga akan sangat terkait erat dengansejauh mana mereka menjalankan prinsip-prinsipatau disiplin organisasi pembelajar sebagaimanatelah diuraikan. Berdasarkan kerangka fikir ini,maka fenomena berhasil tidaknya suatu programHKm di suatu tempat dapat ditelusuri melaluipelaksanaan masing-masing peran pemangkukepentingan, melalui pendekatan pelaksanaanprinsip-prinsip organisasi pembelajar pada masing-masing organisasi pemangku kepentingan di atas.Dari serangkaian uraian di atas, secara skematik,pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai-mana disajikan dalam Gambar 1.
Berdasarkan peraturan Hutan Kemasyarakatanyang terakhir, yaitu Permenhut Nomor :P.37/Menhut-II/2007, yang kemudian mengalamitiga kali perubahan, yaitu melalui PermenhutNomor P.18/Menhut-II/2009, NomorP.13/Menhut-II/2010 dan Nomor P.52/Menhut-II/2011, di dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa ruanglingkup pengaturan HKm meliputi: (1) penetapanareal kerja hutan kemasyarakatan, (2) perizinandalam hutan kemasyarakatan, (3) hak dankewajiban, (4) pembinaan, pengendalian danpembiayaan, dan (5) sanksi. Berdasarkan peraturantersebut dapat diidentifikasi peran masing-masingpemangku kepentingan sebagaimana terlihat padaLampiran 1.
Gambar 1. Kerangka pendekatan penelitian organisasi pembelajarFigure 1. Research framework of learning organization
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
89
B. Lokasi Penelitian
Metode Pengumpulan Data
Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) provinsi yaituProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ProvinsiLampung dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaipelaksana kebijakan Hkm. Ketiga provinsi tersebutdipilih karena keberadaan program HKm denganberbagai tingkat perkembangan. Pada masing-masing provinsi dipilih 1 (satu) kabupaten yangmemiliki kegiatan HKm sebagai representasi. DiProvinsi Nusa Tenggara Barat dipilih KabupatenLombok Utara, dan untuk tingkat tapaknya dipilihHKm yang ada di Desa Santong dan Desa Jenggala.Di Provinsi Lampung dipilih Kabupaten LampungTengah. Sementara di Provinsi Sulawesi Selatandipilih Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi inidilakukan bukan berdasarkan prinsip keterwakilansebagaimana metode sampling di dalam tradisipenelitian kuantitatif melainkan secaraberdasarkan pertimbangan kekhasan fenomenayang ingin diteliti pada masing-masing lokasi,dimana melalui penggalian data dapat ditemukaninformasi yang bermanfaat bagi perbaikankebijakan Hkm.
Penelitian ini berbasis metode penelitiankualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untukmemahami masalah sosial dengan melaporkanpandangan informan secara terperinci dan disusundalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2012).
Metode pengumpulan data yang digunakanadalah teknik observasi, wawancara mendalam,diskusi kelompok dan studi dokumen. Denganmemadukan sedikitnya tiga metode, observasi,wawancara, dan analisis dokumen, maka satu danlain metode akan saling menutupi kelemahansehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebihvalid.
purposive
C.
Wawancara mendalam tetap dilakukan secaraterstruktur dalam upaya memperoleh gambarantingkat pelaksanaan organisasi belajar, yang diukurdengan 5 (lima) karakterisitik atau disiplinorganisasi belajar dari Senge (1990) sebagaimanatelah diuraikan
Penelitian di Provinsi NTB dilakukan pada: (1)Dinas Kehutanan Provinsi NTB, dan (2) KPHRinjani Barat. Kemudian observasi lapangandilakukan ke lokasi HKm di Desa Santong danDesa Jenggala. Di Provinsi Lampung penelitiandilakukan pada: (1) Dinas Kehutanan ProvinsiLampung, (2) Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Lampung Tengah, dan (3) UPT PusatBPDAS Wai Seputih Wai Sekampung, sedangkandi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), penelitiandilakukan terhadap: (1) Dinas Kehutanan ProvinsiSulawesi Selatan, (2) Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bantaeng, dan (3) UPTPusat BPDAS Jeneberang.
Penilaian diupayakan secara partisipatif, dimanapemberian nilai dilakukan secara bersama-samaantara peneliti dan responden. Kriteria jawabanuntuk masing-masing pertanyaan disediakan secaragradasi, sehingga bisa dikuantifikasi menggunakanskala Likert dengan rentang skor 1 - 5 (Soehartono,2004). Angka 1 (=sangat rendah), angka 2(=rendah), angka 3 (=sedang), angka 4 (= tinggi),dan angka 5 (=sangat tinggi). Daftar pertanyaanterstruktur dapat dilihat dalam Lampiran 2. Disamping itu, diajukan pertanyaan-pertanyaan yangterkait dengan kebijakan HKm dan implementasi-nya.
Teknik analisis data dalam proses perumusankebijakan dan penataan organisasi kehutananmengacu pada proses kebijakan ( ) yang
.
policy process
D. Metode Analisis
Gambar 2. Analisis proses pembuatan kebijakan(IDS, 2006)Figure 2. Policy making process
Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
90
dilakukan (IDS, 2006).Proses kebijakan dikembangkan dan dielaborasidari tiga tema yang saling terkait, yaitu: 1)pengetahuan dan diskursus, 2) aktor dan jejaring,dan 3) politik dan kepentingan (Gambar 2).
Kawasan hutan Provinsi NTB seluas1.069.997,78 Ha (53,09% dari daratan ProvinsiNTB) terdiri atas : hutan lindung 447.712,26 Ha,hutan produksi 453.400,54 Ha dan hutankonservasi 168.884,98 Ha. Kemiskinan dan pe-ngangguran penduduk sekitar hutan mendorongterjadinya gangguan keamanan hutan, sedangkankerusakan hutan akan menurunkan kualitaslingkungan yang berakibat pada menurunnyakesejahteraan masyarakat.
Upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomimasyarakat di dalam dan sekitar hutan telahdilakukan oleh para pihak antara lain melaluiPengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM),Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan Lokal(PHTUL) pada hutan produksi , HutanKemasyarakatan (Hkm) dan Pengembangan HutanTanaman Rakyat (HTR) serta Pembangunan HutanTanaman Industri (HTI) oleh investor. KegiatanHkm yang ditetapkan pencadangannya olehMenteri Kehutanan pada tahun 2011 terdapat pada6 (enam) lokasi seluas 4.211 hektar. Kegiatan yangdilaksanakan pada lokasi tersebut mencakupfasilitasi perijinan, kelembagaan masyarakat,bantuan bibit dan pembuatan tanaman.
Permasalahan yang menonjol di ProvinsiLampung adalah alih fungsi lahan hutan menjadiperuntukan lain, misalnya perkebunan, tambak,pertanian, pemukiman, dan lain-lain; perambahanhutan dan pembalakan liar khususnya di kawasanhutan lindung dan kawasan suaka alam danpelestarian alam. Untuk mengatasi berbagaipersoalan tersebut, upaya yang dilakukan adalahmelibatkan masyarakat sekitar hutan untuk turutmenjaga kelestarian hutan dan melaksanakanprogram HKm sebagai salah satu jawaban untukmengatasi permasalahan tersebut. Hal ini
Institute of Development Studies
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Hkm
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Provinsi Lampung
dikarenakan melalui HKm maka masyarakatdilibatkan dalam pengelolaan dan penjagaan hutan.
Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 per-kembangan HKm di Lampung cukup maju. Hal inidibuktikan dengan adanya penetapan areal kerjaHkm oleh Kementerian Kehutanan seluas42.695,39 Ha (50,3 persen) dari total target HKmProvinsi Lampung seluas 85.000 Ha (tahun 2007)yang terdiri dari 47 kelompok Pemegang IzinUsaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKm) yang tersebar di lima kabupaten.
Hingga tahun 2011, usulan pencadangan arealHKm dari Bupati kepada Kementerian Kehutanandi Provinsi Lampung mencapai 37.916,406 Haterbagi pada 27 kelompok di Kabupaten LampungTengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan WayKanan. Usulan areal pencadangan ini telahdiverifikasi oleh tim dari Kemenhut, dan hasilnyasemua kelompok layak mendapatkan Izin UsahaPemanfaatan HKm selama 35 tahun. Namun sejakdua tahun lalu hingga saat ini ijin dari Menteribelum keluar.
Sejarah pembangunan HKm di Sulawesi Selatansudah lama, yaitu pada dasawarsa 1993 - 2003.Pada saat itu konsepnya masyarakat yang berada didalam kawasan hutan diberi hak kelola hutan setiapKK 2 Ha, dipadukan dengan program Reboisasidan Rehabilitasi Lahan. Bila pohon yang ditanamtumbuh sampai 80% diberikan hak pungut.Masyarakat diwajibkan menanam pohon sesuaiprogram RRL dan secara bersamaan diper-bolehkan memanfaatkan lahan untuk tanamanpertanian (agroforestri). Kepada mereka diberikansurat hak kelola dan dapat melaksanakan panen.Program ini tidak berlanjut pada periode Gubernurberikutnya, karena dari pemerintah pusat sudahdiintroduksi kebijakan Hkm. Semenjak ituberkembanglah HKm, HTR dan Hutan Desa.
Pengukuran pelaksanaan prinsip-prinsip ataudisiplin organisasi belajar dari Senge (1990)dilakukan dengan menggunakan metodewawancara terstruktur dan penilaiannya dilakukansecara partisipatif antara peneliti denganresponden. Berdasarkan hasil wawancaraterstruktur diperoleh hasil penilaian sebagaimanatercantum pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.
3. Provinsi Sulawesi Selatan
B. Penilaian Organisasi Pembelajar
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
91
Tabel 2.Skor organisasi belajar pada instansi pemerintah di Provinsi NTBTable 2. Learning organization scores at government agencies in NTB Province
Tabel 3. Skor organisasi belajar pada intansi pemerintah di Provinsi LampungTable 3. Learning organization scores at government agencies in Lampung Province
Prinsip Learning Organization
Instansi Pemerintah (Government Agency)
Dinas Kehutanan Provinsi
Nusa Tenggara BaratKPH Rinjani Barat
Personal mastery 4 5
Mental model 3 5
Share vision 4 5
System thinking 4 5
Team Learning 4 4
Tabel 4. Skor organisasi belajar pada instansi pemerintah di Provinsi SulselTabel 4. Learning organization scores at government agency in Sulsel Province
Prinsip LearningOrganization
Instansi Pemerintah (Government Agency)
Dinas Kehutanan Provinsi
Sulses
Dinas Kehutanan Kabupaten
Bantaeng
BPDAS Jeneberang
Sulsel
Personal mastery 5 3 5
Mental model 4 5 3
Share vision 4 5 3
System thinking 4 5 4
Team Learning 4 5 4
Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
Prinsip Learning
Organization
Instansi Pemerintah (Government Agency)
Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung
Dinas Kehutanan Kabupaten
Lampung Tengah
BPDAS Wai Seputih Wai
Sekampung
Personal mastery 3 4 5
Mental model 3 4 3
Share vision 3 4 2
System thinking 3 5 4
Team Learning 3 4 3
Berdasarkan Tabel 2, 3 dan 4 pada umumnyaseluruh instansi yang dijadikan sampel telah cukupmemenuhi karakteristik organisasi belajar.Pemenuhan seluruh karakteristik organisasi belajarpada kondisi yang mendekati baik (tinggi) adalahpada organisasi KPH Rinjani Barat.
Sebuah kasus keberhasilan penerapan kebijakanHKm secara empiris ditemukan pada organisasiKPH. Karakteristik merefleksi diri pada individu-
individu organisasi sangat baik ( ,terl ihat dari kemauan para staf untukmeningkatkan kompentensi diri di bidang masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari peran pimpinandalam mewujudkan visi bersama ( ).Kebijakan pimpinan dalam meningkatkankapasitas sumberdaya manusia para stafnya yangcukup berani mengambil keputusan dalamketerbatasan anggaran mencoba mengadakan
personal mastery)
shared vision
( Principle)Learning Organization
(Principle)
Learning Organization
(Principle)
Learning Organization
92JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
pelatihan ( ). Strategi yang cukupcerdik, yaitu setiap ada kunjungan dari instansi lainatau akademisi, mereka dimintakan untukmemberikan pelatihan atau pencerahan terkaitbidang keahlian yang dimilikinya. yangcukup kuat terbangun dalam diri para stafnyawalaupun dengan segala keterbatasan, merekaberusaha untuk bisa meyakinkan diri mereka bahwaprogram dapat memenuhi sasaran. Menurut Karash(2010), diasumsikan bahwa setiap pimpinan akanmeningkatkan tanggung jawabnya dalammenjalankan perannya sebagai manajer sumberdayamanusia di unit kerjanya. Peran manajer/pimpinandalam organisasi pembelajar adalah sebagai gurudan setiap individu diberdayakan agar bertanggungjawab atas kegiatan pembelajaran bagi dirinya.
Akumulasi pengetahuan dari pembelajaran yangkemudian dibagikan kepada anggota organisasilainnya sehingga menjadi pengetahuan tim, yangpada akhirnya para anggota organisasi menjadisaling membutuhkan satu sama lain sehingga ikatanemosional tercipta dalam bertindak sesuai denganrencana kerja ( ). Hal ini dibutuhkankemampuan berkomunikasi dan berkoordinasiyang benar dan tepat. Untuk menjembataninyapimpinan memiliki peranan penting dalammenciptakan iklim tersebut. Begitu pula dengan
sebagai sebuah keterkaitan dan salingketergantungan diantara seluruh fungsi-fungsiorganisasi, dan di KPH Rinjani Barat telahterwujud, yaitu dengan adanya kondisi bahwasemuanya bekerja dalam satu kesatuan di dalamsebuah sistem.
Figur kepemimpinan ( ) di KPH RinjaniBarat sangat kuat mempengaruhi keberhasilansuatu program. Dengan kepemimpinannya telahmampu menggerakkan para stafnya untukmencapai visi misi, walaupun jumlahnya tidaksebanding dengan luasan areal kerjanya. Posisinyasebagai pemimpin tidak menutup kemungkinan-nya untuk turun ke lapangan dan berinteraksi secaralangsung dengan masyarakat pelaku HKm maupunmasyarakat desa sekitar dan di dalam kawasanhutan. Kepercayaan telah terbangun dari carapendekatan personal kepada masyarakat maupunpara stafnya.
Di dalam diri seorang pemimpin perlu terpenuhitiga kompetensi utama yaitu kompetensi teknis,
dan etis (Kartodihardjo 2012). Denganmakna bahwa baik buruknya kebijakan ditentukanoleh perilaku. Perilaku yang buruk akan
inhouse training
Mental models
team learning
system thinking
leadership
leadership, ,
menghasilkan pengelolaan sumberdaya politik,ekonomi, dan administrasi yang buruk pula.
Secara keseluruhan informasi yang diperolehdari ketiga provinsi tersebut, bahwa karakteristikorganisasi pembelajar yang sangat kritis untukdiperbaiki adalah Kesulitan para stafdalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misidari organisasi tersebut. Mereka hanya sekedarmengetahui secara teks saja tetapi di dalammengamalkannya masih terdapat kendala.Disinilah peranan pimpinan yang memilikikompetensi teknis, dan etis sangat besar.
Dari pengalaman tersebut tergambarkan bahwamenurut Garvin (1993), budaya belajar danorganisasi belajar dapat sukses diterapkan dalamorganisasi bisnis, ada enam budaya belajar yangperlu dibangun, yaitu:1. Informasi dibagi dan mudah diakses.2. Dalam budaya belajar, data dan informasi tidak
diperlakukan secara rahasia atau ditumpuk olehpara pemimpin. Tetapi mudah diakses, sehinggaatasan dan bawahan saling berbagi informasidan memiliki kerangka referensi yang sama.
3. Pembelajaran dikembangkan dan bernilai.4. Dalam organisasi pembelajar, pelatihan dan
pembelajaran merupakan hal yang prioritas.5. Kesalahan atau kegagalan tidak dihukum.6. Individu diharapkan Belajar Secara Konstan
Permasalahan penerapan organisasi belajar diKemenhut sebagai salah satu pembuat kebijakanpemerintah adalah organisasi belajar belummenjadi produk , dan organisasi belajarini hanya sebatas wacana saja. Hal ini dapat terlihatjelas dari berbagai permasalahan dalam penerapankebijakan HKm yang sebetulnya telah lama muncul( s e j a k d i k e l u a r k a n P. 3 7 / 2 0 0 7 ) y a n gmengakibatkan capaian HKm relatif rendah yaituterkait:
Peraturan perundangan; terdapat dua ijin dalamsatu kegiatan yaitu ijin pemanfaatan/pengelolaan (IUPHKm), dan ijin pemanfaatankayu (UIPHHK Hkm).Inkonsistensi kebijakan dari strata pusat(Kemenhut) sampai ke pemerintah daerah.Dukungan anggaran; dimana alokasi APBDPemda hanya sebagian kecil.
HKm menurut P.37/Menhut-II/2007merupakan sebuah program pemberdayaan
shared vision.
leadership,
affirmative
a.
b.
c.
C. Pelaksanaan Kebijakan Hkm
93Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau disekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitassosial dengan kesamaan mata pencaharian yangbergantung pada hutan dan aktivitasnya dapatberpengaruh terhadap ekosistem hutan. Tanggungjawab pusat di dalam mempertahankan hutanberdasarkan fungsi ekologi yang harusdikolaborasikan dengan upaya memberikandistribusi manfaat hutan kepada masyarakat sesuaiamanat UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.Walaupun otonomi daerah telah dilakukan,sinergitas antara pusat (Kemenhut) dan daerah(Dishut Kab, Dishut Prov) tetap perlu dibina karenaadanya sebagian tanggung jawab pusat terhadapfungsi dan keberadaan kawasan hutan.
Untuk mengupas permasalahan-permasalahanyang terjadi pada HKm dalam konteks prosespembuatan kebijakan perlu difahami adanyaketerlibatan unsur-unsur yang saling terkait satusama lain, yaitu narasi/diskursus, aktor/jaringan,dan politik/kepentingan (IDS 2006; Sutton 1999).
Dalam hal ini terdapat 4 (empat) situasi yangdialami para aktor terkait kebijakan HKm, yaitusebagai berikut:
Situasi yang dialami Pembuat Kebijakan(Pemerintah Pusat)Kebijakan tidak hanya cukup diartikan sebagai
peraturan perundangan saja. Kebijakan merupakansuatu resep atau solusi yang dapat mengobatipenyakit atau masalah kebijakan, sehingga lingkupkebijakan juga menyangkut kemampuan pembuatresep untuk melakukan indentifikasi penyakit yangbenar.
Selama ini diakui para pembuat kebijakan telahdibekali oleh pengetahuan teknis kehutanan yangcukup rasional sehingga dalam meramu teks sebagaisuatu aturan main tidak diragukan lagi jika dilihatdari sudut pandang ilmu kehutanan ( )Tidak dapat dipungkuri oleh para pembuatkebijakan Hkm bahwa secara keilmuan diturunkandari konsep-konsep pengelolaan hutan alam yangdilakukan modifikasi. Diskursuscukup kuat tertanam di lingkungan para pembuatkebijakan sehingga pengelolaan HKm yangmelibatkan masyarakat dengan sejumlahpengetahuan dan kapasitas yang terbatas disamakandengan pengusaha besar yang mengelola hutanalam.
Terkait dengan kebijakan HKm yaitu diatur
1.
scientific forestry .
scientific forestry
dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Ke-masyarakatan yang di dalamnya terdapat pasal 21yang berisi aturan main permohonan Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanKemasyarakatan (IUPHHK HKm). Salah satuklausal di dalamnya terkait kewenangan Menteriuntuk menerima atau menolak permohonantersebut. Akan tetapi selama ini permohonan yangmasuk lebih dari 3 (tiga) tahun masih belum adakeputusan ditolak atau diterima, sehinggaIUPHHK HKm belum ada satupun yangdikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
2. Situasi yang dialami Pelaksana Kebijakan(Pemerintah Daerah)Pengalaman empiris umumnya mekanisme
penetapan kebijakan yang tergali sangat minim dansecara keseluruhan dapat dikatakan tidak ada. Jikaada terkadang tidak jelas dalam hal ruang danintensitas keterlibatan mereka. Terkait keterlibatanmereka dalam proses tersebut kebanyakan hanyamenerima draft aturan, atau tidak jarang pada saatdraft yang telah mendapat masukan dari pelaksanakebijakan yang sangat mengetahui persis kondisisesungguhnya di lapangan tidak diakomodirmasukannya. Menurut mereka seolah hanya salahsatu bentuk formalitas saja dalam prosespembuatan kebijakan. Bahkan tak jarang pulapelaksana kebijakan lebih banyak menerima aturanyang sudah final disusul sosialisasi bagaimanapelaksanaannya. Pada akhirnya kondisi tersebutakan menimbulkan kesulitan bagi para pelaksanakebijakan dalam melaksanakan aturan tersebut.Dari pengalaman itu, mereka menilai bahwa tidakada mekanisme penetapan kebijakan yang jelas.Dinilai pula bahwa tidak ada mekanisme partisipasipublik dan atau konsultasi publik dalamperencanaan, penyiapan, dan penetapan kebijakanatau peraturan perundangan selama ini.
Beberapa pengalaman para pelaksana kebijakanyang mendapatkan mandat sesuai P.37/2007,bahwa program HKm didelegasikan kepadadaerah baik untuk melakukan fasilitasi maupunanggarannya diserahkan kepada daerah dan inibersifat wajib. Pusat membagi pekerjaan kepadadaerah dan lupa dengan anggaran yang harusdisediakan sehingga menjadi beban daerah.
Dalam situasi tertentu, beberapa pelaksanakegiatan yang cukup tinggi idealismenya berusahauntuk mewujudkan program tersebut tanpa
94JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
menimbulkan konflik di lapangan. Seperti halnyapada saat kondisi yang ada di lokasi tersebut telahterjadi pengelolaan lahan di kawasan hutan olehmasyarakat (perambahan), pelaksana kebijakanberusaha melakukan pendekatan kepadamasyarakat dengan menawarkan skema HKm. Bilamasyarakat menolak skema tersebut maka merekatidak dilarang dan dibiarkan mengelola tetapidilakukan pendekatan agar mereka mengelola lebihdisesuaikan dengan konsep pengelolaan HKm.Dengan pendekatan demikian cenderung akanberhasil baik dalam perlindungan terhadap kawasanmaupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ditinjau dari aturan yang berlaku saat ini haltersebut menghadapkan pelaksana dan masyarakatpada situasi pelanggaran hukum kehutanan, yaitumenggunakan/memanfaatkan kawasan hutantanpa ijin.
Situasi yang dialami Masyarakat Pelaku HkmMasyarakat pelaku HKm pada beberapa tempat
cenderung telah mengenal program - programsejenis yang telah diluncurkan, sehingga bagimereka tidak asing lagi dan cenderung berhasil didalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapidengan sejumlah persyaratan yang dimandatkandalam P.37/2007, seperti dengan diwajibkannyapara pemegang IUPHKm untuk membuat rencanakerja yang terdiri dari rencana umum dan rencanaoperasional. Untuk menyusun sendiri masyarakattidak mampu, maka dibantu oleh pendampingmaupun pelaksana kebijakan (petugas lapangan).Akan tetapi kesulitan cukup berat dihadapi untukmembuat rencana kerja tersebut, karena untukmembuat rencana kerja yang dikatakan harusmencapai kelestarian pada pola agroforestritersebut tidak semudah pada hutan alam. Padaakhirnya dengan macetnya penyusunan rencanakerja tersebut masyarakat belum dapat mengajukanIUPHHK HKm. Hal ini membuat masyarakatkurang bersemangat untuk mendaftarkan kawasanhutan yang telah digarap ke dalam skema HKm,karena mereka melihat contoh kasus yang telahmelaksanakannya namun belum bisa menikmatihasil kayunya.
Situasi yang dialami Masyarakat PendampingHkmPada saat program HKm diluncurkan, pihak
pihak yang dapat membantu pelaksanaan fasilitasiadalah perguruan tinggi, lembaga keuangan,
3.
4.
koperasi, BUMN/BUMS/BUMD, dan LSM.Tetapi pada umumnya pelaksanaan fasilitasi inidilakukan oleh LSM saja. Cukup terasa manfaatnyadengan dilakukan pendampingan oleh LSMtersebut. Masyarakat lebih terbuka pengetahuan didalam berorganisasi maupun di dalam pengelolaanhutan. Akan tetapi bantuan yang diberikan hampirsebagian bersifat keproyekan, dimana pada saatproyek masih berlangsung kegiatan pendampinganterus dilaksanakan, namun setelah proyek berakhirkegiatan pendampingan terhenti. Dan tidak jarangdampak dari kondisi seperti ini mengakibatkanterjadinya kemunduran kegiatan tersebut.
Narasi kebijakan HKm ditopang oleh teoriilmiah yang mengakar dan menggunakanpendekatan metodologis. Kebijakan HKm iniseolah - olah subyek yang akan diatur olehmasyarakat pelaku HKm yang memiliki kapasitasdan kapabilitas yang tinggi dan hampir disamakandengan pengaturan pada pengelolaan hutan alamdimana subyeknya adalah pengusaha yang memilikikapital dengan kapasitas dan kapabilitas tinggi.Narasi yang dilahirkan berasal dari diskursus
, yaitu terdapat empat doktrin yangmembentuk kerangka dasar berfikir bagipendidikan kehutanan dan memiliki status hukumdibanyak negara, yaitu doktrin kayu sebagai unsurutama ( ), kelestarian hasil (
), jangka panjang ( ), dan standarmutlak ( ). Penjelasan keempatdoktrin tersebut adalah sebagai berikut:
Doktrin menemukan pembenaran ideologis melalui apa yang disebutsebagai “ ” (Gluck 1987), yangmenyatakan bahwa barang dan jasa lainnya darihutan mengikuti dari belakang hasil kayusebagai hasil utama. Kandungan konseptualteori ini dianggap tidak memadai dan tidakmemberikan opsi-opsi bagi ragam praktekpengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidakmemberikan penjelasan mengenai tujuankeberadaan hutan, sebal iknya hanyamemberikan penilaian keberadaan hutandengan kayu sebagai urutan pertama.Doktrin dianggap sebagai inti dariilmu kehutanan yang didasarkan pada "etikakehutanan" yang membantu menghindarimaksimalisasi keuntungan sepihak daneksklusif dan menghargai hutan yang pentingbagi keberadaan manusia (Gluck danPleschbeger, 1982). Doktrin ini mungkin
scientific forestry
timber primacy sustainedyield the long term
absolute standard
timber primacy;
wake theory
sustained yield;
a. -
b.
95Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
mengaburkan antara hutan yang mempunyaimanfaat bagi publik ( ) danharus di-lestarikan manfaatnya itu, denganhutan dapat dimiliki oleh perorangan (
), sehingga keputusan memanfaatkan hutanmenjadi pilihan pemiliknya. Akibatnyapelestarian hutan dapat dipaksakan kepadapemilik hutan, dan apabila pemilik hutanmenolak, ia justru akan meng-konversi hutannyamenjadi bukan hutan.Doktrin yaitu kekhasan kehutananadalah periode rotasi yang panjang. Ini memaksar imbawan untuk memper t imbangkankonsekuensi jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, pendekatan ke-hutanan dilakukan dengan hati-hati (cenderungtidak dinamis) atau konservatif dan engganuntuk menerima kepentingan sosial baru didalam hutan.Doktrin mengandung arti lebihdaripada memahami hutan sebagai obyekpengetahuan ilmiah (hukum-hukum alam darihutan). Doktrin ini termasuk ide bahwa yangpaling mengetahui tujuan manajemen hutanadalah rimbawan, dan kehutanan yang menjadimediator antara hutan dan pemiliknya ataumasyarakat. Orang tidak memiliki kepentinganyang berbeda di hutan, tetapi hutan memiliki -setidaknya dalam literatur hutan Eropa Tengah -berbeda "fungsi" untuk masyarakat. Denganmenggunakan istilah "fungsi", orang berbalikdari subjek menjadi objek dan hutan menjadisubjek.Doktrin yang dikemukakan diatas perlu ditinjau
dan disesuaikan dengan tingkat perkembanganmasyarakat yang bersinggungan dengan kawasanhutan seperti dalam program Hkm.
Kesimpulan dari kajian organisasi belajar diKementerian Kehutanan dan instansi pemerintahdi daerah adalah sebagai berikut:
Instansi pelaksana HKm (Dinas Kehutananpropinsi, kabupaten, UPT Pusat) secara umummemenuhi karakteristik organisasi belajar padaberbagai tingkatan. Kondisi yang mendekatiideal (tinggi) adalah pada organisasi KPH
public goods and services
privaterights
the long term;
standard absolute;
c.
d.
1.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
KesimpulanA.
Rinjani Barat dengan skor
. Hal ini cukup kuat di-pengaruhi oleh figur kepemimpinan ( )dimana dalam dirinya telah terpenuhi tigakompetensi utama yaitu kompetensi teknis,kepemimpinan, dan etis sehingga organisasibelajar dapat terwujud.Titik kritis dalam perbaikan organisasi sesuaikarakteristik organisasi belajar adalah .Pada umumnya organisasi yang menjadi sampelmengalami kesulitan dalam menerjemahkandan menjalankan visi misi dari organisasi.Narasi kebijakan HKm dilahirkan berasal daridiskursus (doktrin kayu sebagaiunsur utama ( ), kelestarian hasil( ), jangka panjang ( ) danstandar mutlak ( ) sehinggapengaturan subyeknya (masyarakat pelakuHKm) dianggap memiliki kapasitas dankapabilitas yang memadai.Instansi pelaksana kebijakan HKm masihm e n g a l a m i ke s u l i t a n d a l a m m e n g -implementasikan kebijakan Hkm karenaberdasarkan gambaran situasi pelaksanakebijakan sangat lemah di dalam melakukanperubahan ruang kebijakan ( ).
Perlu adanya sosialisasi secara sistematis dari sisikonseptual maupun implementasi (pengalamanempiris) tentang organisasi belajar pada pelakuatau instansi yang terlibat dalam kebijakan danimplementasi HKm. Hal ini antara lain dapatdilakukan melalui pintu kurikulum pelatihanpegawai dan peningkatan budaya organisasi.Perumusan kebijakan HKm perlu dilakukansecara partisipatif dan akuntabel denganmelibatkan para pihak, terutama unsur PembinaHKm di daerah dan perwakilan masyarakatpelaku Hkm.
Anonim. 2012. Hutan Kemasyarakatan Dan HutanDesa Mampu Meningkatkan KesejahteraanDan Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dariwebsite:
.
system thinking(5),personal mastery (5), mental models (5), shared vision(5), team learning (4)
leadership
shared vision
scientific forestrytimber primacy
sustained yield the long termabsolute standard
policy space
2.
3.
4.
1.
2.
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
http://ppid.dephut.go.id/bt_hutan kemasyarakatan.htm
96JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry AndResearch Design: Choosing Among FiveTraditions. London: SAGE Publications.
Dunn, W.N. 1994. Public Policy Analysis: AnIntroduction. Second Edition. Prentice-HallInc. New Jersey. 687 pp.
Dwiyanto, A. 2011. Mengembalikan kepercayaanpublik melalui reformasi birokrasi. Jakarta:Kompas Gramedia.
Garvin, DA. 1993. Building learning organization.Harvard Business Review 73:78-91.
Gluck, P. 1987. Social Value in Forestry. Ambio 16(2/3): 158-160.
IDS. 2006. Understanding Policy Processes AReview of IDS Research on the Environment.Knowledge, Technology and Society Team.UK: Institute of Development Studies at theUniversity of Sussex Brighton BNI 9RE.
Karash, R. 2010. Learning Organization Overview.[terhubung berkala]: //
.www.humtech.com/
opm/grtl/Loo/Loo.cfm [10 Apr 2010]
Kartodihardjo, H. (Ed). 2012. Kembali Ke Jalanyang Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu danPraktek Kehutanan Indonesia. ForciDevelopment. Bogor.
Scott, W.R. 2008. Institutions and organizations.Ideas and interests.California: SagaPublications.
Senge, P.M. 1990, The Fifth Discipline: The Artand Practice of the Learning Organization.New York: Doubleday.
Senge, P.M. 1996. Leading learning organizations.50:36-37.
Soehartono, I. 2004. Metode Penelitian Sosial.Suatu Teknik Penelitian Bidang Ke-sejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Sutton, R. 1999. Policy Process: An Overview.Working Paper 118.Overseas DevelopmentInstitute. London SW1E 5 DP: PortlandHouse. Stag Place.
Training and Development
Lampiran 1. Peran pemangku kepentingan dalam kebijakan HKm berdasarkan peraturanAppendix 1. Role of stakeholders in Hkm based on regulations
Aspek(Aspect)
Pemangku Kepentingan(Stakeholders)
Kemenhut(MoF)
Gubernur(Governor)
Bupati(District head)
LSM(NGO)
UPT Pusat(Technicalexecuting unit)
Masyarakat(Community)
PenetapanArealKerja
Membentuk TimVerifikasi danmelakukan verifikasi
Menetapkan ArealKerja HKm
Membuat timverifikasi, drunsur Dishut
Mengajukanpenetapan kpdMenteri
Membuat timverifikasi, drunsur Dishut
Mengajukanpenetapan kpdMenteri
Mendampingi timverifikasi
Memfasilitasimasyarakatsetempatdlmmembuatpermohonan
Mengajukan permohonankpd Bupati/Gubernur
Perijinan MengeluarkanIUPHHK-HKm
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
MemberikanIUPHKm
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
MemberikanIUPHKm
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
Membentuk kelompok tanidan koperasi
Hak dankewajiban
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
Melakukanfasilitasi kpdmasyarakat
PengembanganKelembagaan danKemitraanPengelolaanDaerahAliranSungai
Hak:a. mendapat fasilitasib. memanfaatkan hasil hutan
non kayu,c. memanfaatkan jasa
lingkungand. memanfaatkan kawasane. memungut hasil hutan
kayu
Kewajiban:a. melakukan penataan
batas areal kerjab. menyusun rencana kerjac. melakukan penanaman,
pemeliharaan, danpengamanan
d. membayar provisisumberdaya hutan sesuaiketentuan
e. menyampaikan laporankegiatan pemanfatanhutan kemasyarakatankepada pemberi izin.
PembinaandanPengendalian
Membina danmengendalikankebijakan HKmyang dilaksanakanGubernur/Bupati
Menyusunpedomanpenyelenggaraanpemanfaatanhutankemasyarakatan,melakukanmonitoring danevaluasi
Membinadanmengendalikan kebijakanHKm yangdilaksanakanBupati
Memberikanbimbingan,arahan dansupervisi,monitoring,dan evaluasi
Melakukanfasilitasi melaluikegiatanpendampingan,monitoring danevaluasi secarapartisipatif
Pembiayaan Menyediakan danaAPBN
Menuediakandana APBDProv
Menyediakandana APBD Kab
Mengusahakandarisumber2 lain
Sanksi Bisa menerbitkansanksi terkaitIUPHHK-HKm
Bisamenerbitkansanksi terkaitIUP-HKm
Bisamenerbitkansanksi terkaitIUP-HKm
97Organisasi Belajar dan Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Hariyatno Dwiprabowo, Mulyaningrum, Eno Suwarno( )
Lampiran 2. Struktur pertanyaan atas organisasi belajar
a) Bagaimana latar belakang pendidikan karyawan di unit kerja ini?b) Bagaimana pelaksanaan diklat reguler untuk karyawan?c) Adakah pengaruhnya terhadap kinerja karyawan?d) Media apa saja yang disediakan oleh kantor untuk meningkatkan kapasitas karyawan?e) Adakah dukungan iklim yang kondusif untuk peningkatan belajar karyawan?
a) Bagaimana tingkat keyakinan atau rasa percaya diri karyawan untuk mewujudkan visi misi unit kerja?b) Bagaimana sikap mental karyawan ketika menghadapi situasi sulit atau hambatan-hambatan yang
pernah dialami?c) Bagaimana sikap mental karyawan dalam mensikapi perubahan-perubahan lingkungan organisasi?d) Bagaimana gambaran tingkat rasa percaya diri para karyawan dalam mengemban tugas-tugas sesuai
dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan?
a) Apakah unit kerja ini sudah memiliki visi-misi bersama?b) Bagaimana proses pembentukan visi misi ini?c) Seberapa tinggi usaha sosialisasi dan pemahaman karyawan terhadap visi-misi ini?d) Bagaimanakah kadar komitmen pimpinan untuk merealisasikan visi-misi ini?e) Seberapa lancar kesinambungan visi-misi antar generasi?f) Adakah pengaruh visi-misi terhadap konerja personal karyawan maupun tim?
a) Apakah Tupoksi besar sudah dibagi-bagi habis kepada unit-unit di bidang ini?b) Apakah unit-unit kerja sudah diisi oleh orang-orang yang kompeten?c) Bagaimana tingkat kecukupan jumlah karyawannya?d) Bagaimanakah kelancaran koordinasi di dalam unit kerja maupun dengan unit kerja lain?e) Bagaimanakah tingkat sinergisitas di antara unit-unit kerja?f) Seberapa kuat langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat sinergisitas?
a) Seberapa tinggi di unit kerja ini terjadi proses belajar bersama (tim)? Bagaimana bentuk pelaksanaan-nya?
b) Seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja organisasi?c) Seberapa banyak kecukuan literatur pendukung untuk meningkatkan pengetahuan karyawan?d) Bagaimanakah tingkat dokumentasi pengalaman-pengalaman pelaksanaan pekerjaan di masa lalu?e) Seberapa tinggi terjadi proses saling berbagi pengetahuan antar karyawan?f) Seberapa jauh terjadi proses transfer pengetahuan antar generasi?
Appendix 2. Structured questionnaire of learning organization
1. Personal Mastery
2. Mental Model
3. Shared Vision
4. System Thinking
5. Team Learning
98JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 85 - 98
CADANGAN KARBON HUTAN LINDUNG LONG KETROKDI KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR
UNTUK MENDUKUNG MEKANISME REDD+(
)Carbon Stocks of Protection Forest in Malinau District, East
Kalimantan to Support REDD+ Mechanism
Yonky IndrajayaBalai Penelitian Teknologi Agroforestry
Jl. Raya Ciamis-Banjar km 4, Ciamis 46201, email:
iterima 22 Januari 2013, direvisi 25 April 2013, disetujui 2 Mei 2013
Kegiatan konservasi hutan lindung (HL) melalui mekanisme REDD+ merupakan salah satu kegiatan yangsangat potensial untuk dapat menurunkan emisi global. Menjaga HL dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutandapat mencegah hutan untuk mengemisi karbondioksida. Informasi tentang jumlah cadangan karbon hutan lindungyang belum terganggu (hutan perawan) penting sebagai base line dan untuk mengetahui potensi penyerapannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi cadangan karbon yang tersimpan dalam biomassa tegakan hutanlindung Long Ketrok, yaitu hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat desa Setulang, Kabupaten Malinau, ProvinsiKalimantan Timur. Metode perhitungan cadangan karbon yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dengan menggunakan persamaan allometrik yang telah dibangun di hutan tropis. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa jumlah karbon tersimpan dalam hutan lindung Long Ketrok adalah 304 ton/ha yang terdiri darikarbon tersimpan dalam biomassa di atas permukaan tanah sebesar 255 ton/ha, biomassa akan sebesar 42 ton/ha,dan nekromassa sebesar 7 ton/ha. Proporsi batang, cabang, akar, dan daun dalam biomassa karbon berturut-turutsebesar 70,7%, 14,6%, 14,1% dan 0,6%.
Kata kunci: Biomassa, karbon, hutan lindung
1
1
D
ABSTRACT
Conservation on protection forests through REDD+ mechanism is one of the potential activities that can reduce global emission.Preserving protection forest from deforestation and forest degradation can prevent forests to emit carbon dioxide. Information on carbonstocks in virgin forest is important for baseline and to know its potential sequestration. This paper aims to discern the potency of carbonstocks in biomass of Long Ketrok protection forest managed by Setulang community, located in Malinau East Kalimantan. The methodused in this research is non-destructive using allometric equations developed in tropical forests. Result of this study showed that carbonstored in biomass of Long Ketrok protection forest is 304 ton/ha, consisting of C stored in aboveground biomass (255 ton/ha), rootbiomass (42 ton/ha), and necromass (7 ton/ha). The proportion of stem, branch, root, and leaf carbon biomass are: 70.7%, 14.6%,14.1% and 0.6% respectively.
Keywords: Biomass, carbon, protection forest
non-destructive
ABSTRAK
99Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
I. PENDAHULUAN
Pemanasan global telah terjadi yang di-indikasikan oleh peningkatan suhu udara rata-rataselama 30 tahun terakhir (IPCC, 2007). Pemanasanglobal menyebabkan terjadinya perubahan iklim,antara lain dengan meningkatnya frekuensi maupunintensitas terjadinya cuaca ekstrim seperti badaitropis, El-Nino La-Nia, perubahan pola hujan,perubahan pola angin, perubahan salinitas air lautdan lain-lain. Selain itu, perubahan iklim dapat pula
berdampak pada perubahan masa reproduksihewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuranpopulasi, frekuensi serangan hama dan penyakit,serta berbagai perubahan pada ekosistem di daerahlintang yang tinggi dan ekosistem pantai (IPCC,2007).
Pemanasan global dipicu oleh peningkatankonsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti COX,NOX, SOX, dll yang bersumber dari proses alamidan kegiatan manusia. Kontribusi kegiatanmanusia dalam peningkatan emisi global telah
100JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 - 109
menjadi perhatian dunia dan telah dibicarakandalam pertemuan-pertemuan internasional.Negara-negara di dunia telah berkomitmen untukmengurangi konsentrasi GRK di atmosfer yangdituangkan dalam kesepakatan dalam konferensipara pihak sepertimisalnya Protokol Kyoto.
Tingkat emisi Indonesia menurut data tahun2000 berada pada peringkat 15 dunia apabila tidakmemperhitungkan emisi akibat perubahanpenggunaan lahan dan kehutanan/
(LULUCF), dengan tingkatemisi sebesar 503 Mt Co (Baumert , 2005).Apabila emisi dari kegiatan perubahan penggunaanlahan dan kehutanan dimasukkan dalamperhitungan, maka Indonesia berada pada peringkatke-3 dunia dengan emisi dari sektor LULUCFsebesar > 2.500 Mt CO (Baumert , 2005). Olehkarena itu, Indonesia telah berkomitmen untukmengurangi laju emisinya sebesar 26% secarasukarela dan sebesar 41% dengan bantuan asinghingga tahun 2020 (Perpres 61/2011) dengansektor kehutanan sebagai kontributor tertinggidalam penurunan tersebut.
Laju pengurangan emisi dari penurunan tingkatdeforestasi dan degradasi hutan dikenal denganREDD (
) yang pertama kali diperkenalkan padaCoP ke 13 di Bali pada tahun 2007. Pada tahun 2010,pada CoP ke 16 di Cancun, kegiatan lain yang diakuisebagai langkah pengurangan emisi sektorkehutanan adalah peningkatan karbon stok hutan,konservasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari.Tambahan kegiatan ini memberikan tambahantanda ”+” pada REDD menjadi REDD+.Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisitelah tertuang dalam Rencana Aksi NasionalPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)melaui Perpres No 61 Tahun 2011. Sektorkehutanan akan berkontribusi dalam penurunanemisi GRK sebesar 0,672 Giga ton (skenario 26%)atau 1,039 Giga ton (skenario 41%).
Hutan lindung yang merupakan kawasan hutanyang memiliki sifat khas yang mampu memberikanperlindungan kepada kawasan sekitar maupunbawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahbanjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah(Kepres 32/1990) juga mendapatkan perhatiandalam RAN GRK, di mana deforestasi dandegradasi hutan juga terjadi di kawasan hutan
(CoP/Conference of Parties)
Land Use, LandUse Change and Forestry
et al.
et al.
Reducing Emissions from Deforestation and forestDegradation
2
2
lindung (Harris , 2008). Oleh karenanya,menjaga hutan lindung dari perambahan dandegradasi berperan dalam mengurangi emisikarbon (HL bebas emisi). Rencana aksi yang terkaitdengan hutan lindung adalah pengembanganpemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangankawasan konservasi, ekosistem esensial danpembinaan hutan lindung (Perpres 61/2011).Target penurunan emisi dari penguranganperambahan hutan konservasi dan hutan lindungdi 12 propinsi prioritas termasuk Kaltim dalamkurun waktu 5 (lima) tahun (2010 - 2014) adalahsebesar 49,77 juta ton.
Penelitian yang dilakukan oleh Harris(2008) menyebutkan bahwa laju deforestsi diKalimantan Timur di kawasan yang dilindungiadalah 230.720 ha dengan potensi emisi sebesar305 juta ton CO dari tahun 2003 hingga 2013dengan asumsi laju deforestasi tetap sama tanpaada tindakan pengurangan. Tingkat emisi yangterjadi per tahun rata-rata adalah sebesar 30 juta tonCO . Apabila dibandingkan dengan targetpenurunan emisi yang kurang lebih sebesar 50 jutaton CO , provinsi Kaltim memiliki kontribusi yangcukup besar dalam target penurunan emisi ini.
Untuk mengetahui tingkat emisi GRK dariperubahan penggunaan lahan yang terjadidiperlukan informasi tentang faktor emisi (yaitunilai rata-rata emisi karbondioksida/CO yangterjadi akibat perubahan penggunaan lahan) dandata aktivitas (luas perubahan yang terjadi). Tulisanini bertujuan untuk mengetahui potensi cadangankarbon yang tersimpan dalam biomassa tegakanhutan lindung Long Ketrok di Kalimantan Timuruntuk mengisi gap informasi terkait dengan faktoremisi GRK dari sektor kehutanan, terutama hutanlindung. Hutan Lindung Long Ketrok merupakansalah satu hutan lindung yang sebagian wilayahnyadikelola oleh masyarakat adat Desa Setulang, yanghingga saat ini berupaya untuk memperolehmanfaat hutannya dari jasa lingkungan (Wunder
, 2008)
Iklim di lokasi penelitian termasuk dalam tipe Amenurut klasifikasi Schmidt and Ferguson (1951),dengan bulan basah lebih dari 9 (sembilan) bulan
et al.
et al.
etal.
2
2
2
2
.
II. METODE PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
101
yang terjadi antara bulan April - Desember, danbulan kering selama kurang dari 2 (dua) bulan(Samsoedin , 2009). Rata-rata curah hujanadalah sebesar 3.828 mm/ tahun dengan suhutertinggi sebesar 34 C dan terendah sebesar 23,5 C,dengan kelembaban udara berkisar antara 75-98%(Samsoedin , 2009).
Formasi geologi di lokasi penelitian termasukdalam formasi batuan pegunungan, dansediment (Machfudh, 2002). Jenis tanah di lokasipenelitian termasuk dalam alluvial gleik, gleisoleutrik dan podsolik ortoksik (Machfudh, 2002).Ketinggian tempat di lokasi penelitian berkisarantara 150-500 m dpl. (Sidiyasa , 2006).
et al.
et al.
methamorfic
et al.
o o
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di hutan lindung (HL)Long Ketrok, yang sebagian wilayahnyamerupakan hutan adat Desa Setulang, KabupatenMalinau, Provinsi Kalimantan Timur. Di hutanlindung Long Ketrok yang juga merupakan wilayahHutan Desa Setulang, masih terdapat pohon-pohon yang berukuran sangat besar (diameter >200 cm). Masyarakat Desa Setulang beranggapanbahwa menjaga hutan akan memberikan dampakyang menguntungkan bagi masyarakat yaitu dapatmencegah banjir, menjaga kualitas air dan menjagakesuburan tanah desa karena posisi desa yangberada di hilir sungai dan hutan adat berada di hulu
Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
Gambar 1. Lokasi hutan lindung Long Ketrok, Kab. Malinau, Prov. KalimantanTimur
Figure 1. Long Ketrok Protection Forest, Malinau, East Kalimantan
102
(Sidiyasa , 2006). Kepedulian masyarakat yangamat tinggi terhadap lingkungan telah menarikperhatian para peneliti baik di Indonesia maupundari luar negeri untuk meneliti hubunganmasyarakat dengan hutan.
Pengumpulan data dilakukan pada bulanNovember - Desember 2010. Lokasi HL LongKetrok disajikan dalam Gambar 1.
Data dikumpulkan dari petak ukur berukuran 20x 20 meter sebanyak 114 buah atau kurang lebih4,56 ha. Penentuan lokasi sampel dilakukanberdasarkan informasi awal dari nilai indeksvegetasi (NDVI) yang telah dilakukan sebelumnya.Titik sampel yang telah ditentukan kemudiandiklarifikasi dengan penduduk Desa Setulang dimana lokasi hutan yang tidak terganggu olehmasyarakat. Jumlah plot yang dibuat adalahsebanyak 114 buah. Semua pohon dengan ukurandiameter ≥ 10 cm diukur kelilingnya dandiidentifikasi jenisnya. Pohon dengan diameterkurang dari 10 cm tidak dihitung dalam penelitianini. Selain itu, nekromassa atau biomassa matiseperti pohon yang rebah dan pohon yang matiberdiri juga diukur keliling dan panjangnya. Dalampenelitian ini tidak tidak dihitung karbon yangtersimpan di dalam seresah dan tanah.
Lokasi penelitian ini berada di tanah mineral.Cadangan karbon tanah mineral relatif tetap (IPCC,2006), maka perhitungan cadangan karbon hutanhanya dilakukan pada biomassa di atas tanah (
) dan biomassa di bawahpermukaan tanah ( ). Estimasibiomassa pohon banyak dilakukan denganpersamaan allometrik, yaitu menduga berat seluruhpohon berdasarkan salah satu ukuran dimensipohon (misalnya diameter pohon). Beberapapersamaan allometrik telah dikembangkan dandigunakan dalam menghitung biomassa pohondalam tegakan hutan alam Dipterokarpa (Yamakura
, 1986; Brown, 1997; Chave , 2005; Basuki, 2009).Perhitungan biomassa pohon di atas tanah
( ) dalam penelitian ini dilakukan denganmengikuti persamaan yang dibuat oleh Yamakura
et al.
AboveGround Biomass/AGB
Below Ground Biomass
et al. et al. etal.
AGBet
C. Pengumpulan data
D. Metode Pengukuran Kandungan KarbonBiomassa
al.
DH
dalam et al
D
w
w
w
w
et al.
et al
(1986) yang telah melakukan penelitian di hutantropis Kalimantan Timur. Pendekatan yang diambildalam menghitung biomassa pohon di ataspermukaan tanah adalah dengan membagi pohonke dalam beberapa fraksi, yaitu: batang, cabang,dan daun. Tinggi pohon diestimasi dari hubunganantara diameter pohon (dalam centimeter)dengan tinggi (dalam meter) mengikutipersamaan yang dibuat oleh Ogawa dan Kira(1977) Yamakura . (1986), yaitu:
Di mana 4,5 cm. Tinggi hasil estimasi daripersamaan (1) dan nilai pengukuran diameterpohon selanjutnya dipergunakan untukmengestimasi berat kering batang (dalamkilogram) dengan persamaan:
Selanjutnya, berat kering batang hasil estimasidari persamaan (2) dipergunakan untukmengestimasi berat kering cabang (dalamkilogram) dengan persamaan:
Berat kering batang dan cabang hasil estimasi daripersamaan (2) dan (3) dipergunakan secarabersama-sama dalam mengestimasi berat keringdaun (dalam kilogram) mengikuti persamaan:
Sebagai pembanding, persamaan allometrik dalampersamaan 5 yang dibuat oleh Chave (2005)dan persamaan 6 yang dibuat oleh Brown (1997)juga digunakan:
Karena perhitungan biomassa akar sulit dilakukan,maka biomassa akar diestimasi mengikutipersamaan yang dibuat oleh Cairns . (1997),yaitu:
Setelah mengetahui berat kering tiap fraksi pohon,cadangan karbon dalam biomassa diasumsikansebanyak 0,5 dari total berat kering tiap fraksi.
S
S
B
L
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 - 109
103
Nekromass (biomassa mati) dihitung denganmenggunakan persamaan dari Hairiah (2011),yaitu:
Dimana merupakan berat kering nekromass(dalam kg), adalah diameter, adalah panjangnekromass, dan adalah berat jenis (rata-rata beratjenis pada penelitian ini adalah 0,68 g/cm ).
Berdasarkan pengukuran pada 114 petak ukur,struktur tegakan HL Long Ketrok mengikutibentuk J terbalik yaitu jumlah individu pohon padakelas diameter terkecil adalah terbanyak dansemakin berkurang dengan bertambahnya kelasdiameter pohon. Struktur seperti ini menunjukkanhutan dalam keadaan normal, seperti disajikandalam Gambar 2.
Komposisi jenis tegakan di hutan Malinau telahdilaporkan oleh beberapa peneliti seperti misalnyaSidiyasa (2006) dan Sheil (2010). Penelitianini mengikuti jalur yang telah dibuat oleh CIFORdan komposisi jenis di HL Long Ketrok telahdilaporkan oleh Sidiyasa (2006). Beberapajenis pohon yang ada di HL Long Ketrok antaralain: Meranti Merah ( sp.), Meranti Putih
et al.
ND H
et al. et al.
et al.
Shorea
3
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Struktur Tegakan dan Komposisi Jenishutan lindung Long Ketrok
( sp.), Majau ( ), Ulin( , Tengkawang (terutama
dan ), Kajen Ase( ), Keruing ( sp.),Darah-darah ( sp.), Kapur (
), dan Meranti Kuning ( sp.). JenisMeranti Merah dan Meranti Putih mendominasikomposisi tegakan di HL Long Ketrok denganINP berturut-turut sebesar 20,47% dan 20,45%(Sidiyasa , 2006).
Penelitian lain di hutan alam di Malinaumenyebutkan bahwa suku Dipterocarpaceaemendominasi baik pada jumlah pohon maupunkerapatan bidang dasarnya. Beberapa jenis pohondari suku Dipterocarpaceae diantaranya adalah
,spp (
) dan spp. () berkontribusi terhadap lebih dari
50% kerapatan bidang dasar total (Sheil , 2010).Sementara itu, penelitian yang dilakukan di hutanalam di Berau juga menemukan bahwa kontribusisuku Dipterocarpaceae terhadap kerapatan bidangdasar total adalah sebesar 48% (Sist and Saridan,1999).
Beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi danbanyak digunakan oleh masyarakat Desa Setulangadalah atau daun sang yang banyakdigunakan untuk membuat anyaman topi, tikar,
Shorea Shorea johorensisEusideroxylon zwageri)
Shorea macrophylla S. beccarianaMedhuca spectabilis Dipterocarpus
Myristica Dyobalanopsaromatica Shorea
et al.
Anisoptera grossivenia Dipterocarpus lowii, D. stellatus,Shorea . S. agami, S. atrinervosa, S. brunnescens, S.exelliptica, S. macroptera, S. maxwelliana, S. ochracea, S.parvifolia, S. pauciflora, S. pinanga, S. rubra, S.venulosa , Vatica V. albiramis, V. granulata,V. Umbonata
et al.
Licuala valida
(9)
Gambar 2. Struktur tegakan hutan lindung Long KetrokFigure 2. Stand structure of Long Ketrok protection forest
Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
104
dsb.; sp. atau talas hutan yang banyakdigunakan untuk sayur, pohon buah-buahan,tumbuhan obat, dan lain-lain (Sidiyasa , 2006).Ares ( ), salah satu tumbuhanyang dilindungi menurut SK Menteri Pertanian No.54/Kpts/Um/2/1972 juga banyak ditemukan ditempat terbuka. Pohon tengkawang yang dulupernah menjadi primadona karena memberikankeuntungan ekonomi yang tinggi banyak jugaterdapat di Hutan Desa Setulang.
Beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi diHutan Desa Setulang adalah:(Ulin) (Tengkawang)
(Tengkawang Rambai)(Tengkawang Tengkal/Tengkawang Burung)
(Tengkawang Terendak)(Jelutung) (Ketipai)
(Banggeris)(Pangi/Kepayang) (Gaharu)
(Rotan Merah)(Rotan Sega) (Rotan Lilin)
(Rotan Semule)(Rotan Gelang) (Sidiyasa , 2006).
Hasil dari perhitungan cadangan karbondisajikan dalam Tabel 1. Pohon dengan diameterbesar (> 60 cm) hanya berjumlah 24 batang/ha(Gambar 2) namun berkontribusi lebih kurang 67%dalam menyimpan karbon dalam biomassa di ataspermukaan tanah yaitu sebanyak 171 ton C/ha(Gambar 3). Sementara itu, pohon berdiameter
Alocasia
et al.Duabanga moluccana
Eusideroxylon zwageri, Shorea macrophylla , Shore
pinanga , Shorea beccariana,
Shorea seminis , Dyeracostulata , Palaquium gutta ,Koompassia excelsa , Pangium edule
, Aquilaria beccariana ,Korthalsia echnometra , Calamus caesius
, Calamus javanensis ,Calamus pogonocanthus , Daemonoropssabut et al.
B. Karbon Tersimpan dalam Biomassa
kecil (< 60 cm) yang berjumlah 480 batang/ha,hanya berkontribusi sebesar 33% dalampenyimpanan karbon dalam biomassa di ataspermukaan tanah, yaitu sebesar 84 ton C/ha(Gambar 3).
Apabila terjadi perambahan hutan, dimanapohon dengan kelas diameter >60 cm dipanen, dandiasumsikan 50% dari pohon yang berada di kelasdiameter ini adalah jenis komersial (Bertault andSist, 1997), dan tingkat kerusakan yang terjadiakibat kegiatan pembalakan liar adalah 50% (Sist
, 2003), maka potensi cadangan karbon yangakan hilang adalah sebesar kurang lebih 149 tonC/ha pada saat terjadi perambahan. Potensikehilangan ini berasal dari pohon ditebangsebanyak 12 pohon DBH >60 cm (85 ton/ha), danpohon yang mati (64 ton/ha) .
Penelitian ini menggunakan beberapapersamaan allometrik biomassa untuk bisadibandingkan dengan penelitian lain yangmenggunakan metode yang sama. Penelitian initidak bisa memberikan justifikasi atas persamaanallometrik yang memberikan hasil estimasi palingmendekati kenyataan karena tidak dilakukannyapengukuran biomassa secara langsung di lapangan(penerapan metode ).
etal.
non-desctructive sampling
1
2
1 Pembalakan yang dilakukan diasumsikan mengikuti teknik konvensional dimanakerusakan tegakan tinggal (yaitu pohon terluka dan mati) akibat kegiatan ini adalahkurang lebih 50% dari kondisi tegakan awal.2 Sist (2003) menyebutkan bahwa dari kerusakan tegakan tinggal, proporsi pohonyang mati dan terluka masing-masing adalah sebesar 50%. Dalam penelitian ini, totalkarbon tersimpan dalam biomassa di atas permukaan tanah adalah sebesar 255 tonC/ha, sehingga total karbon tersimpan dalam biomassa pohon mati adalah sebesar 50%x 50% x 255 = 64 ton C/ha.
et al.
Gambar 3. Karbon tersimpan dalam biomassa pohon beberapa kelas diameterFigure 3. Carbon stored in tree biomass in several diameter classes
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 - 109
105
Tab
el1.
Kar
bo
nte
rsim
pan
dal
amb
iom
assa
di a
tas
per
muka
anta
nah
HL
Lo
ng
Ket
rok
Tab
le1.
Car
bon
stor
edin
abov
egr
ound
biom
ass
ofL
ong
Ket
rok
Pro
tect
ion
For
est
Persamaanallometrik() allometricequation
Kel
asd
iam
eter
(Dia
met
erclas
s)T
ota
l(
)T
otal
10-
20cm
21-3
0cm
31-4
0cm
41-5
0cm
51-6
0cm
61-7
0cm
71-8
0cm
81-9
0cm
91-1
00cm
≥10
1cm
N/
ha
367
6927
1311
54
44
7D
rata
-rat
a23
2535
4555
6676
8795
125
Chave
TA
GB
(kg/
ph
n)
144
485
1160
2234
3563
5641
7890
1079
113
385
2454
0T
AG
B(t
on
/h
a)30
3431
3041
3131
3850
183
Kar
bo
n(t
on
/
ha)
1416
1514
1915
1518
2386
234
Brown
TA
GB
(kg/
ph
n)
129
404
949
1830
2946
4754
6789
9527
1207
523
995
TA
GB
(to
n/
ha)
2728
2624
3426
2733
4517
9K
arb
on
(to
n/
ha)
1313
1212
1612
1316
2184
211
Yamakura
Tin
ggi
rata
-rat
a33
2936
4246
5053
5658
63B
atan
g(k
g/p
hn
)12
644
010
5020
1431
9950
4570
4596
3611
965
2217
0C
aban
g(k
g/p
hn
)19
7518
937
661
499
514
1619
7324
8247
69D
aun
(kg/
ph
n)
49
1626
3751
6582
9615
1T
AG
B(k
g/p
hn
)15
052
312
5524
1638
4960
9185
2711
691
1454
427
090
Kar
bo
n(t
on
/
ha)
1517
1615
2116
1619
2595
255
Sum
ber
: dat
ap
rim
er(s
ourc
e)(p
rim
ary
data
)
Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
106
Tabel 2 menunjukkan karbon tersimpan dalamnekromassa di lokasi penelitian yang terdiri dari 63batang dalam plot yang diamati (atau 14 batang/ha)dengan diameter antara 8 - 137 cm dan panjangantara 6 - 32 meter. Total karbon dalam nekro-massa per ha berdasarkan persamaan (9) adalah 7ton/ha.
Tabel 3 metode Yamakura (1986)menunjukkan karbon tersimpan dalam biomassahutan lindung Long Ketrok cukup tinggi yaitu 304ton/ha. Proporsi karbon tersimpan dalambiomassa hutan tertinggi berada pada biomassa diatas tanah dengan karbon tersimpan hingga 255ton/ha. Sementara itu, estimasi karbon tersimpandalam biomassa di bawah permukaan tanah (akar)
et al.
adalah sebesar 42 ton/ha. Walaupun tidak adakegiatan oleh manusia di dalam hutan, secaraalami pohon seperti halnya makhluk hidup lainakan mati karena usia maupun karena faktoralam seperti terkena penyakit atau petir. Karbontersimpan dalam nekromassa hutan lindungLong Ketrok adalah sebesar 7 ton/ha, yangsebagian besar berupa pohon yang secara alamimati dan tumbang. Karbon tersimpan dalamnekromassa yang ada di dalam HL Long Ketrokini relatif kecil karena tidak adanya kegiatanpenebangan oleh manusia. Karbon tersimpandalam nekromassa pada hutan bekas tebangancukup tinggi, yaitu lebih dari 50 ton/ha (Indrajaya,2012).
Tabel 2. Nekromassa di HL Long KetrokTable 2. Necromass in Long Ketrok Protection Forest
Jumlah batangper ha (
) (N/ha)Number of
stems
Keliling rata-rata( )
(cm)Average girth
Diameter rata-rata( )
(cm)Average Diameter
Panjang rata-rata( )
(m)Average length
Karbon rata-rata per ha(
)(ton/ha)Average carbon stored in
necromass per ha
14 100 32 15 7Sumber : data primer(source) (primary data)
Tabel 3 . Karbon tersimpan dalam biomassa HL Long KetrokTable 3. Carbon stored in biomass of Long Ketrok Protection Forest
PersamaanAllometrik(AllometricEquation)
Karbon atas tanah(Carbon in AGB) /
ton ha-1
Karbon Akar(Carbon in RB)/
ton ha-1
Karbon dalamNekromassa
(Necromass) / tonha-1
Total Karbon dalam biomass(Total carbon stored in biomass) /
ton ha-1
AGB RB Nec Tot = AGB+RB+Nec
Chave 234 39 7 280
Brown 211 36 7 254
Yamakura 255 42 7 304
70.70%
14.56%
0.61%
14.14%
Batang
Cabang
Daun
Akar
Gambar 4. Proporsi karbon tersimpan dalam biomassa HL Long KetrokFigure 4. Proportion of carbon stored in biomass of Long Ketrok protection forest
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 - 109
107
et al.
et al.
et al.
et al.
et al.
et al.
Penelitian perhitungan cadangan karbon dihutan alam tak terganggu telah pula dilakukan dibeberapa tempat di Kalimantan Timur, antara lain:di hutan wilayah PT Inhutani II, pada hutan primersebelum penebangan, jumlah karbon yangtersimpan dalam biomassa adalah sebesar 264ton/ha (Samsoedin , 2009). Penelitian lain diKabupaten Nunukan yang dilakukan oleh ICRAF,menunjukkan bahwa karbon tersimpan dalambiomassa tegakan hutan alam adalah sebesar 230ton/ha (Rahayu , 2006). Kedua penelitian inihanya memperhitungkan karbon tersimpan dalambiomassa di atas permukaan tanah, dan keduanyamenggunakan persamaan Chave (2005).Apabila dibandingkan dengan penelitian ini denganpersamaan Chave (2005), karbon tersimpan diatas permukaan tanah adalah sebesar 234 ton/ha.
Dari karbon yang ada di dalam biomassa, fraksipohon yang memiliki cadangan karbon tertinggiadalah berurutan adalah batang, cabang, akar, dandaun dengan persentase sebesar 70,7%, 14,56%,14,14% dan 0,61 % (Gambar 4).
Pada dasarnya hutan akan memberikan manfaatlingkungan (perlindungan DAS, konservasikeanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon)yang dapat dinikmati oleh para penerima manfaatapabila dalam kondisi tidak terganggu. Pihakpenerima manfaat lingkungan perlindungan DASadalah masyarakat yang tinggal di hilir sungai dimana hutan di hulu sungai berada (Pagiola ,2002). Kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran airsungai di hulu dipengaruhi oleh kondisi hutan dihulu DAS. Sementara itu, penerima manfaatlingkungan HL sebagai penyimpan karbon dankonservasi keanekaragaman hayati adalahkomunitas internasional (Pagiola , 2002).
Dalam konteks HL yang berperan sebagaipenyimpan karbon, beberapa upaya perlindunganuntuk menghindari deforestasi dan degradasi hutanyang dapat dilakukan antara lain:
Kontrol terhadap hama dan penyakitberkoordinasi dengan lembaga penelitian sepertiBalitbang Kehutanan dan Dinas KehutananKabupaten MalinauPerlindungan terhadap para penjarah hutanterutama pelaku illegal logging dengan patrolikeamanan rutin oleh petugas pengamanandidukung oleh partisipasi masyarakat
C. Upaya Pemanfaatan HL Bebas Emisi
Meminimalisir kegiatan tebang dan bakar padaperladangan berpindah yang dilakukan olehmasyarakatMemberikan kompensasi yang cukup apabilaternyata di dalam kawasan HL terdapat potensicadangan mineral yang bernilai tinggi.Upaya-upaya yang dilakukan yang bertujuan
untuk meminimalisir emisi dari hutan lindungdapat berjalan beriringan dengan kegiatan yangbertujuan untuk perlindungan terhadap keane-karagaman hayati. Untuk membiayai kegiatanperlindungan HL di atas, diperlukan insentif daripihak penerima keuntungan ( )antara lain melalui meknaisme
. Inisiatif imbal jasalingkungan (PES) yang telah dilakukan olehmasyarakat Desa Setulang adalah dengan menjualjasa lingkungan keanekaragaman hayati. Namun,inisiatif ini menemui kendala antar lain:keterbatasan waktu yang dimiliki oleh donor dansulitnya memenuhi prinsip (Wunder
, 2008). PES REDD memiliki keunggulan dalamhal jelasnya tujuan yang ingin dicapai yaitupenurunan emisi dengan cara mengurangi lajudeforestasi dan degradasi hutan yang dapat diukurdengan metode yang jelas (Blom , 2010).Dengan semakin baiknya kondisi hutan danmenurunnya laju deforestasi, jasa lingkungan lainseperti perlindungan keanekaraman hayati pundapat diperoleh.
Upaya untuk menjual jasa lingkungan karbonpun telah dilakukan awalnya dengan bekerja samadengan sektor swasta dan telah dipresentasikan diBali dalam ke 13. Namundemikian, upaya ini pun masih menemui kendalaterutama terkait dengan payung perundangan yangada. Upaya kemudian dilanjutkan dengan bekerjasama dengan GIZ (lembaga bantuan teknis dariJerman) melalui program FORCLIME (Forest andClimate Change Programme) yang didanai olehKfW (Bank Pembangunan Jerman) untuk menjualjasa lingkungan karbon dari HL Long Ketrok ini.
Dari hasil analisis tentang karbon tersimpandalam biomassa tegakan hutan lindung LongKetrok dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
beneficiary partiesPayment for
Environmental Services (PES)
conditionality etal.
et al.
Conference of Parties
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
KesimpulanA.
Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
108
1.
.
Hutan Lindung Long Ketrok telah memberikanmanfaat lingkungan bagi warga Desa Setulangsebagai pengatur tata air dan hasil hutan nonkayu seperti rotan, buah-buahan, tanaman obat-obatan, sayur, dsb.Komposisi jenis HL Long Ketrok adalah UlinTengkawang Tengkawang Rambai TengkawangTengkal/Tengkawng Burung TengkawangTerendak Jelutung Ketipai BanggerisPangi/Kepayang Gaharu Rotan Merah RotanSega Rotan Lilin Rotan Semule Rotan Gelang.Estimasi total karbon tersimpan dalam biomassahutan lindung Long Ketrok menurut metodeYamakura (1986) adalah 304 ton/ha denganjumlah karbon di atas permukaan tanah sebesar255 ton/ha, karbon tersimpan dalam akarsebesar 42 ton/ha, dan karbon tersimpan dalamnekromassa sebesar 7 ton/ha, sementara itu,karbon tersimpan dalam biomassa di ataspermukaan tanah, dalam akar, dan nekromassmenurut metode Chave (2005), berturut-turut adalah: 234, 39, dan 7 ton/ha, sedangkanmenurut metode Brown. (1997) karbontersimpan dalam biomassa di atas permukaantanah, dalam akar, dan nekromass berturut-turutadalah: 211, 36, dan 7 ton/ha.Perbedaan hasil perhitungan estimasi karbontersimpan dalam biomassa tegakan terjadikarena metode yang digunakan berbeda.Pemilihan metode dapat dilakukan berdasarkanskenario optimis dan pesimis, dimana metodeYamakura (1986) dengan hasil estimasitertinggi dapat digunakan sebagai skenariooptimis. Sedangkan, metode Brown (1997)dengan hasil terendah dapat dipergunakansebagai skenario pesimis.
5. Proporsi fraksi pohon batang, cabang, akar, dandaun dalam biomassa hutan lindung LongKetrok berturut-turut adalah: 70,70%, 14,56%,14,14%, dan 0,61%
Penelitian ini menunjukkan bahwa total karbonyang tersimpan dalam biomassa hutan alam tidakterganggu cukup bervariasi dan tidak seragamseperti yang ditunjukkan dalam nilai dalamTier 1. Untuk dapat memberikan gambaran tentangvariasi jumlah karbon tersimpan dalam biomassategakan hutan alam tidak terganggu skala nasional,perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada zonaekologi yang berbeda
2.
3.
4.
,, ,
,, , , ,
, , ,, , ,
et al.
et al.
et al.
default
B. Saran
Ucapan terima kasih
DAFTAR PUSTAKA
Penulis mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada Yuli Nugroho danKresno Dwi Santosa yang telah membantu penulisdalam pengambilan data di lapangan. Penulis jugamengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnyakepadaatas dukungan dana dan fasilitas alat yangdiberikan, sehingga kegiatan penelitian ini dapatdilaksanakan dengan baik.
Basuki, T.M., van Laake, P.E., Skidmore, A.K.,Hussin, Y.A., 2009. Allometric equations forestimating the above-ground biomass intropical lowland Dipterocarp forests. ForestEcology and Management 257, 1684-1694.
Baumert, K.A., Herzog, T., Pershing, J., 2005.Navigating the numbers: Greenhouse gasdata and international climate policy. WorldResorce Institute.
Bertault, J.G., Sist, P., 1997. An experimentalcomparison of different harvestingintensities with reduced-impact andconventional logging in East Kalimantan,Indonesia. Forest Ecology and Management94, 209-218.
Blom, B., Sunderland, T., Murdiyarso, D., 2010.Getting REDD to work locally: lessonslearned from integrated conservation anddevelopment projects. EnvironmentalScience and Policy.
Brown, S., 1997. Estimating Biomass and BiomassChange of Tropical Forests: a Primer. In.FAO, Rome.
Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H.,Baumgardner, G.A., 1997. Root biomassallocation in the world's upland forests.Oecologia 111, 1-11.
Chave, J., Andalo, C., Brown, S., Cairns, M.A.,Chambers, J.Q., Eamus, D., Folster, H.,Fromard, F., Higuchi, N., Kira, T., Lescure,J.P., Nelson, B.W., Ogawa, H., Puig, H., Riera,B., Yamakura, T., 2005. Tree allometry andimproved estimation of carbon stocks and
Tropenbos International Indonesia Programme
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 99 - 109
balance in tropical forests. Oecologia 145, 87-99.
Hairiah, K., Ekadinata, A., Sari, R.R., Rahayu, S.,2011. Pengukuran cadangan karbon daritingkat lahan ke bentang lahan. WorldAgroforestry Center, Bogor Indonesia.
Harris, N.L., Petrova, S., Stolle, F., Brown, S., 2008.Identifying optimal areas for REDDintervention: East Kalimantan, Indonesia asa case study. Environmental Research Letter3.
Indrajaya, Y., 2012. Cadangan karbon hutan bekastebangan pembalakan berdampak rendahdan konvensional di Kalimantan Timur:Studi kasus hutan Malinau. Jurnal PenelitianSosial dan Ekonomi Kehutanan 9, 21-30.
IPCC, 2006. IPCC Guideline 2006 Guidelines fornational green house gas inventories.
IPCC, 2007. Climate change 2007: Impacts,adaptation, and vulnerability. In: Parry, M.,Canziani, O., Palutikof, J., Linden, P.v.d.,Hanson, C. (Eds.), Contribution of WorkingGroup II to the Fourth Assessment Reportof the Inter Governmental Panel on ClimateChange. IPCC.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung.
Machfudh, 2002. General description of theBulungan Research Forest. In, Technicalreport phase I 1997-2001 ITTO Project PD12/97 Rev.1 (F) Forest, Science andSustainability: The Bulungan model forest.CIFOR, Bogor Indonesia.
Pagiola, S., Landell-Mills, N., Bishop, J., 2002.Market-based mechanisms for forestconservation and development. In: Pagiola,S., Landell-Mills, N., Bishop, J. (Eds.), SellingForest Environmental Services: Market-based mechanism for conservation anddevelopment. Earthscan, London.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61tentang Rencana Aksi Nasional Gas RumahKaca.
Rahayu, S., Lusiana, B., Noordwijk, M.v., 2006.Pendugaan cadangan karbon di ataspermukaan tanah pada berbagai sistempenggunaan lahan di kabupaten Nunukan,Kalimantan Timur. ICRAF, Bogor-Indonesia.
Samsoedin, I., Dharmawan, I.W.S., Siregar, C.A.,2009. Potensi biomassa karbon hutan alamdan hutan bekas tebangan setelah 30 tahundi hutan penelitian Malinau, KalimantanTimur. Jurnal Penelitian Hutan danKonservasi Alam VI, 47-56.
Sheil, D., Kartawinata, K., Samsoedin, I., Priyadi,H., Afriastini, J.J., 2010. The lowland foresttree community in Malinau, Kalimantan(Indonesian Borneo): results from a one-hectare plot. Plant Ecol Divers 3, 59-66.
Sidiyasa, K., Zakaria, Iwan, R., 2006. Hutan DesaSetulang dan Sengayan Malinau, KalimantanTimur: Potensi dan identifikasi langkah-langkah perlindungan dalam rangkapengelolaannya secara lestari. CIFOR,Bogor Indonesia.
Sist, P., Saridan, A., 1999. Stand Structure andfloristic composition of a primary lowlandDipterocarp forest in East Kalimantan.Journal of Tropical Forest Science 11, 704-722.
Sist, P., Sheil, D., Kartawinata, K., Priyadi, H., 2003.Reduced-impact logging in IndonesianBorneo: some results confirming the needfor new silvicultural prescriptions. ForestEcol Manag 179, 415-427.
Wunder, S., Campbell, B., Frost, P.G.H., Sayer, J.A.,Iwan, R., Wollenberg, L., 2008. WhenDonors Get Cold Feet: the CommunityConservation Concession in Setulang(Kalimantan, Indonesia) that NeverHappened. Ecol Soc 13.
Yamakura, T., Hagihara, A., Sukardjo, S., Ogawa,H., 1986. Aboveground Biomass of TropicalRain-Forest Stands in Indonesian Borneo.Vegetatio 68, 71-82.
109Cadangan Karbon Hutan Lindung Long Ketrok di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur untuk ..... Yonky Indrajaya( )
PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGANHUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARA BARAT DAN
DESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR(
)
The Roles of Customary Law in Forest Management and Protectionin Sesaot Village, West Nusa Tenggara and Setulang Village,
East Kalimantan
MagdalenaPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jalan Gunung Batu No.5, Bogoremail: [email protected]
iterima 22 Januari 2013, direvisi 1 Mei 2013, disetujui 17 Mei 2013
Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitarhutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah beragumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokalakan mendukung pengelolaan hutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukumadatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalampengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang digunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yangdidominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah(Kalimantan Timur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan 30pegawai pemerintah, 20 LSM dan 50 penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adat masih berperandalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas,hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasan hak masyarakat terhadap hutan, transparansi danakuntabilitas keuangan.
Kata kunci: Pengelolaan dan perlindungan hutan, masyarakat lokal, hukum adat, faktor-faktor
1
1
D
ABSTRACT
The challenges of forest management and protection In Indonesia often come from local community who live around the forest.However, some studies have argued that customary practices of local community will support sustainable forest management. This researchwas to study 'how do local people and their customary law protect and manage their forest?' as well as to analyze determinant factors ofcustomary law applied in forest management and protection. The methods used were case study of two villages, that is, Sesaot Village,dominated by Sasak People (West Nusa Tenggara) and Setulang Village, dominated by Dayak Kenyah People (East Kalimantan).Data was collected through field observation and interviews with 30 government offials, 20 NGO staff and 50 villagers. The study foundthat the existence of customary forest was significant in protecting and sustaining forest management. Factors that determined itssustainability were mainly cohesivity, kinship relationship, the present support of various stakeholders, clear property right as well asfinancial transparency and accountability.
Keywords: Forest management and protection, local community, customary laws and factors
ABSTRAK
I. PENDAHULUAN
Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutandi Indonesia tersebut seringkali datang darimasyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestari-an pengelolaan hutan sangat tergantung kepadapartisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.Perambahan, , pemanfaatansumberdaya hutan yang tidak lestari, adalah
i l l egal log ging
kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan.Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai
adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragamantara yang satu dan yang lain. Pemberlakukanhukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan.Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapahukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaandan perlindungan hutan misalnya diAwiq-awiqLombok Barat dan hukum adat masyarakat Dayak
110JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
di Kalimantan Timur dalam mengelola hutan adat.Khususnya hukum adat Suku Dayak di KalimantanTimur sangat berperan dalam mengelola danmelindungi hutan adat (Mulyoutami, 2009,Kalimantan Timur, Apomfires (1995).
Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara,khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967telah banyak menimbulkan konflik di tengahmasyarakat yang berkeberatan hutan adatnyadiklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokalberkeinginan memulihkan hak-hak mereka atashutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutannegara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telahmengabaikan hak-hak masyarakat setempat,sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hakmasyarakat lokal untuk mengakses hutan(Sembiring dan Effendi, 1999).
Implementasi otonomi daerah di Indonesia padatahun 2001 diharapkan akan membukakemungkinan baru untuk pengakuan tanah adatseperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999Kehutanan. Namun demikian, peraturanpemerintah yang mengatur hutan adat belum bisaditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarikmenarik kepentingan dalam proses, khususnyaantara Kementerian Kehutanan dan masyarakatsetempat yang diwakili oleh LSM. Negarabermaksud untuk menegakkan beberapapembatasan pada pengakuan resmi tanah adatsementara orang-orang lokal menginginkan tidakada atau pembatasan minimal (ICRAF danKPSHK, 2001; ICRAF 2001)
Situasi ini telah menyebabkan kebuntuan dalammencapai konsensus antara pihak terkait. Beberapakekhawatiran terkait kebijakan memberi hak mutlakkepada masyarakat lokal untuk mengelola lahanhutan adalah kemungkinan pembagian tanah danpenjualan, dominasi oleh elit lokal (Contreras-Hermosilla dan C. Fay, 2005). Juga, ada potensimeningkatnya konflik antara masyarakat, sebagiankarena wilayah Indonesia pedesaan memilikikomposisi multi etnik (Acciaioli, 2006).
Beberapa peneliti telah melaksanakan studimengenai potensi hukum adat dalam pengelolaandan perlindungan hutan lestari.. Salah satunyaadalah, studi mengenai kekayaan pengetahuanMasyarakat Dayak di Kalimantan Timur terhadappemanfaatan tanaman dan ekologi hutan mereka.Mereka juga bersepakat untuk memelihara hutan
et.al.,
et.al., .
bagi generasi mendatang (Mulyoutami, 2009).Berbeda dengan situasi di Kalimantan Timur,Apomfires (1995) melakukan penelitian bagaimanadampak perubahan insitusi adat terhadapkelestarian hutan di Sentani, Papua. Penelitiandimaksud menemukan bahwa rusaknya hutan diSentani disebabkan oleh bergesernya danberubahnya kebudayaan Orang Sentani yangtadinya mengandung kearifan lingkungan.
Seiring dengan maraknya klaim masyarakat adatterhadap hutan, sebuah penelitian tentang klaimhutan dilaksanakan di Luwu, Sulawesi Selatantahun 2008. Studi ini menemukan bahwa klaimterhadap hutan dapat didasarkan bukti-buktisejarah, misalnya kuburan, organisasi adat, kegiatantradisional dalam hutan, serta sebagian masyarakatmasih tergantung pada hutan (Gautama, 2008).
Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupunadat dalam pengelolaan hutan telah berlangsunghampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupunmasyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya,kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaanhutan secara adat semakin menjanjikan. MenteriKehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No.251/Kpts-II/1993 tentang ketentuan pemungutanhasil hutan oleh masyarakat hukum adat atauanggotanya di areal Hak Pengusahaan Hutan.Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/Menhut-II/2004 perihal masalah hukum adat dantuntutan kompensasi/ganti rugi oleh masyarakathukum adat. Kebijakan dimaksud sebagai responatas semakin meningkatnya klaim masyarakat adatterhadap lahan hutan.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telahmemutuskan untuk mengabulkan sebagianpermohonan dari Aliansi Masyarakat AdatNusantara (AMAN), Kesatuan MasyarakatHukum Adat Kenegerian Kuntu dan KesatuanMasyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu(disebut Para Pemohon) dengan disahkannyaKeputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Pemohon telah mengajukan pengujiankesesuaian pasal-pasal dalam UU KehutananTahun 1999 terhadap Undang-Undang DasarTahun 1945, terkait dengan areal hutan negaradalam hutan masyarakat adat. MK mengabulkansebagian permohonan Pemohon yang dituangkandalam 12 butir pernyataan. Hal ini merupakan titikterang terhadap perjuangan pengembalian hutanadat kepada masyarakat hukum adat.
et.al.,
111Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
Menanggapi pro dan kontra terhadappengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal,penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana masyarakat lokal dan hukum adatnyamengelola dan melindungi hutan serta faktor faktoryang mempengaruhinya di Desa Sesaot (KabupatenLombok Barat, Provinsi NTB) dan Desa Setulang(Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur).
II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah studikasus di dua desa, yaitu Desa Sesaot, KabupatenLombok Barat dan Desa Setulang, KabupatenMalinau, Kalimantan Timur (Gambar 1). Pe-ngumpulan data dan informasi dilakukan dengancara wawancara, pengamatan di lapangan maupundari hasil menghadiri pertemuan, lokakaryakehutanan di tingkat lokal dan nasional serta dandata sekunder dari berbagai publikasi.
Wawancara mendalam denganmetode dilakukan terhadap para pihakterkait yaitu dari Kementerian Kehutanan, PemdaKabupaten Lombok Barat dan Malinau, elit lokal(Kepala Desa Setulang dan Sesaot, pemangku adatdi kedua desa), masyarakat lokal di Desat Sesaotdan Setulang dan LSM (CIFOR-Malinau,Konsepsi-Lombok Barat). Dalam metode ,orang yang diwawancarai dapat menyebutkannama lain yang potensial untuk diwawancarai. Totalpeduduk desa yang terlibat dalam wawancaraadalah 50 orang, sedangkan jumlah pegawaipemerintah adalah 30 orang (Staf Pemerintah diTingkat Propinsi dan Kabupaten) dan jumlah stafLSM adalah 20 orang.
Data dan informasi dianalisis secara deskriptifterhadap pemanfaatan lahan dan hasil hutan mau-pun konservasi dan perlindungan. Juga dilakukananalisis terhadap para aktor yang terlibat sertafaktor-faktor yang memengaruhi aplikasi hukumadat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.
(indepth interview)snow ball
snowball
Gambar 1. Lokasi Desa Sesaot dan SetulangFigure 1. Location of Sesaot dan Setulang VillagesSumber: Kementerian Kehutanan, 1997
III. HASIL DAN PEMBAHASANDiskusi pada Bab Hasil dan Pembahasan diawali
dengan gambaran umum dari profil desa,masyarakat dan hutan terkait dua desa yangmerupakan studi kasus penelitian ini. Dilanjutkandengan uraian mengenai pengalaman aplikasihukum adat dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya
diidentifikasi beberapa faktor-faktor yang bisamendukung maupun menghambat aplikasi hukumadat dalam mengelola hutan lestari.
Masyarakat lokal sekitar hutan umumnyabergantung pada hutan sumber mata pencaharian
A. Gambaran Umum
112JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
mereka. Kehidupan mereka masih jauh dari standarsejahtera dengan fasilitas umum (jalan, kesehatan,listrik) yang kurang memadai.
Mayoritas masyarakat lokal Desa Sesaot(berdiri tahun 1968) adalah Orang Sasak (87%)(Badan Pusat Statiatik Indonesia, 2000; Sutedjodan Suryadi 1997). Orang Sasak telah mendominasibudaya Pulau Lombok sejak 1930-an (DepartementVan Economische Zaken, 1935). Mereka tinggaldi desa seluas 41.96 km² dengan kepadatanpenduduk 181 orang per km² (Badan PusatStatistik Indonesia, 2005). Desa mereka terletak8,3 km dari pusat Kecamatan Narmada (BadanPusat Statistik Lombok Barat, 2003). Desa Sesaotterdiri dari 10 dusun, tiga dusun berbatasanlangsung dengan Hutan Sesaot (Gambar 2 dan 3).Mereka telah akrab dengan program-programpembangunan kehutanan dari KementerianKehutanan seperti hutan kemasyarakatan,reboisasi, dan gerhan.
Hutan Sesaot dulunya adalah hutan produksi(Acciaioli, 2006), sehingga masyarakat kehilanganpekerjaan ketika menjadi hutan lindung pada tahun1982. Selanjutnya pembalakan dihentikan, kegiatan-kegiatan ilegal meningkat. Untuk melindungi hutandan kebun HKM mereka , masya raka tmemberlakukan Beberapa pendudukAwiq-awiq.
telah dipenjarakan selama 6 (enam) bulan hinggasatu tahun. Perubahan status hutan telahmenimbulkan masalah ekonomi dan sosial di DesaSesaot.
Di Desa Setulang, mayoritas masyarakatnyaadalah adalah Suku Dayak Kenyah yang tinggal dilahan seluas seluas 85 km (Badan Pusat StatistikKabupaten Malinau, 2006). Dibandingkan denganDesa Sesaot, Desa Setulang lebih terisolasi dandicapai dengan ketinting (perahu panjang) danmemiliki kepadatan lebih rendah dari Desa Sesaot.Populasi Desa Setulang adalah 10-16 orang per km(lebih kecil dari Desa Sesaot), tetapi mereka tidaktersebar merata, dan tinggal berdekatan satudengan yang lain. Penduduk Desa Setulang lebihhomogen dari penduduk Desa Sesaot, dikarenakanmayoritas penduduk Desa Setulang (lebih dari90%) adalah Suku Dayak Kenyah.
Tidak seperti Masyarakat Sesaot, MasyarakatSetulang memiliki hutan adat seluas 53 km², danterletak antara garis lintang utara 3º 23' and 3º 29'and antara garis bujur timur 116 º 24' and 116º 29'(Sidiyasa, 2006). Hutan tersebut merupakanbagian hutan lindung disekitar TN KayanMentarang. Hutan Adat Setulang berjarak 40 menitdengan ketinting (perahu panjang) dari DesaSetulang (Gambar 4 dan 5).
2
2
et.al.,
Gambar 2. Hutan Lindung Sesaot , Lombok BaratFigure 2. Sesaot Protection Forest, in West Lombok DistrictDipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU
113Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
Gambar 3. Sketsa Desa Sesaot dan Hutan SesaotFigure 3. Scetch of Sesaot Village and ForestSumber : Kantor Kelurahan Sesaot, 2006
Gambar 4. Klasifikasi hutan di Kabupaten Malinau, Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 2000Figure 4. The classification of forest in Malinau District designated by Ministry of Forestry of IndonesiaDipetakan oleh Seksi Kartografi, Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS-ANU)
114JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan SesaotAwiq-Awiq
Sehubungan dengan meningkatnya kegiatanilegal di Hutan Desa Sesaot, orang Sasak yang telahmengenal Hukum Adat (asal muasalnyadari Bali), sepakat memberlakukannya padapertengahan tahun 1990an. (KMPH Sesaot, 2000).Ketika itu, Masyarakat Sesaot difasilitasi oleh LSMlokal dan nasional, yaitu Kelompok Mitra PelestariHutan-KMPH; Konsepsi; dan Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial-LP3ES.
diberlakukan untuk melindungiHutan Sesaot dan kebun masyarakat dari tindakanilegal (Tabel 1). Saat itu, Desa Sesaot juga pernahdikenal dengan keberhasilan dalam menjalankanprogram hutan kemasyarakatan (HKM), yang
Awiq-awiq
Awiq-awiq
mengijinkan masyarakat mengelola hutan denganpola agroforestri. Pemberlakuan bersifatsukarela dan sangsi tidak berlaku, khususnya untukorang luar. Pada saat observasi lapangan tidakditemukan dokumen tertulis , tetapiinformasi mengenai proses pelaksanaannya tertulisdi beberapa publikasi dan dapat digali dari hasilwawancara dengan LSM dan masyarakat setempat(Tabel 1).
KMPH (sebuah LSM lokal) dikenal aktif dalamupaya melindungi Hutan Sesaot denganmenggunakan . LSM ini terdiri darikelompok-kelompok petani lokal dari daerahsekitar Hutan Sesaot (KMPH Sesaot, 2000).Kelompok tani seperti KMPH terdapat di negara-negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, NuaiNeua di Thailand. Nuai Neua didirikan untukmenyatukan para petani di Thailand Utara dalam
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Gambar 5. Sketsa Desa Setulang (Kalimantan Timur))Figure 5.Scetch of Setulang Village (East Kalimantan
Sumber: Kantor Kelurahan Setulang dan CIFOR, 2006
No Perihal ( )Subject Keterangan (Remark)1. Sifat pemberlakuan Wajib untuk kelompok Masyarakat Sasak. Sukarela, untuk orang luar, jika
tertangkap biasanya diserahkan kepada yang berwajib.2. Jenis sangsi Pelanggar (dari dalam) dipermalukan di depan masyarakat dan kemungkinan
akan dikucilkan (sangsi bersifat sosial). Untuk orang luar, dilaporkan kepadayang berwajib.
3. Hal-hal yang diatur - Melarang kegiatan yang menggangu areal hutan kemasyarakatan milikpetani setempat
- Melarang pencurian kayu dari hutan lindung4. Cara penetapan
hukumanMelalui pertemuan yang dihadiri KMPH, elit lokal, polisi dan petugaskehutanan. Pertemuan ini akan memutuskan sangsi kepada pelanggar.
Tabel 1. Pemberlakuan di Desa SesaotAwiq-awiqTable 1. Imposing Awiq-awiq in Village
115Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
memperjuangkan keadilan, ketika lahan masyarakatyang ditetapkan sebagai kawasan lindung(Ayuthaya, 1996).
Pelaksanaan memungkinkan opsi,yaitu pertama jika pelaku pelanggaran (misalnyamencuri kayu) adalah anggota HKM maka yangbersangkutan akan diadili di depan masyarakat,pejabat kehutanan dan polisi, untuk diberi sangsi.Kedua, jika pelanggaran dilakukan pihak luar, makaKPMH dan masyarakat akan mengajukan bukti danmelaporkan kepada pihak yang berwenang (sutedjodan Suryadi, 1997).
lebih intensif dilaksanakan ketikameningkatnya kegiatan illegal pada pertengahantahun 1990 (KMPH Sesaot, 2000). Selama satu tahun(1995-1996), enam belas kasus yang melibatkangangguan hutan masyarakat dan pencurian kayudari Kawasan Sesaot dapat diselesaikan olehmasyarakat dan KMPH (Suryadi, 2001).
Ditengah pemberlakukan , KMPHdan masyarakat mengalami tantangan yaitupertama, institusi pemerintah terkait merasaterancam dengan munculnya masyarakat yangmengambil patroli dan sanksi terhadap pelanggarhukum; kedua, KMPH dan masyarakat diklaimtidak memiliki otoritas formal untuk menegakkanhukum (Suryadi, 1998).
Bersadarkan wawancara dengan pengurusKMPH, pemerintah provinsi akhirnya tidak setujudengan cara kerja KMPH dan mereka menyebutnyailegal. Anggota KMPH menjadi lebih kecewadengan tuduhan ini apalagi mereka telah me-
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Awiq-awiq
ngorbankan hubungan baik mereka dengantetangga, teman dan kerabat untuk melindungi hutanMereka juga menyadari bahwa dalam melindungihutan, mereka menempatkan diri mereka sendiridan keluarga mereka beresiko. Pelaksanaan hukumadat akhirnya dihentikan.
Namun demikian, keinginan untuk memberlakukan kembali muncul tahun 2006,dengan melibatkan lebih banyak petani dariberbagai desa. Untuk itu, masyarakat Sasak harusmembangun hubungan baru di tingkat lokal. Halini menunjukan telah mengakar padakehidupan Orang Sasak di Lombok dan sulitdiabaikan. Sayangnya, Hutan Sesaot tidak bisadiselamatkan oleh . Ketika observasilapangan dilaksanakan, Hutan Sesaot telah terbukadan banyak ditanami pisang.
Berbeda dengan Hutan Sesaot, Hutan Setulangmasih “perawan” dan belum banyak dijamah olehprogram pemerintah pusat maupun daerah,termasuk HKM. Status hutan ini merupakanbagian dari hutan lindung, walaupun dalamsejarahnya hutan ini merupakan hutan adat SukuDayak Kenyah.
Dalam mengelola hutan, Suku Dayak Kenyahmemiliki hukum adat yang awalnya didominasioleh para bangsawan, namun kini dilakukan olehsebuah badan yang disebut Badan Pengelola HutanTanek Olen Setulang (BPHTOS). Badan inilah
Awiq-awiq-
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Awiq-awiq
C. Hukum Adat Dayak Kenyah dalamMengelola dan Melindungi Hutan Setulang
Tabel 2. Pemberlakuan hukum adat di Desa SetulangTable 2. Imposing customary law in Setulang Village (Suku Dayak Kenyah)
No Butir hukum adat ( )Point of customary law Keterangan (Remark)1. Sifat pemberlakuan Wajib untuk Masyarakat Dayak Kenyah. Tetapi bersifat sukarela
untuk orang luar.2. Jenis sangsi Pada prakteknya, tidak ada sangsi jelas buat pelanggar dari luar
(perusahaan kayu atau sawit). Biasanya dilakukan penyitaan dankemudian dilaporkan kepada yang berwajib. Masyarakat Dayaksendiri umumnya sangat mendukung perlindungan hutan adatnyadan jarang kena sangsi
3. Hal-hal yang diatur - Pemotongan dan penggergajian kayu di hutan.- Larangan bagi perusahaan penebangan kayu mengadakan
kegiatan di hutan adat.- Pengaturan terhadap perluasan kebun dalam hutan ada.- Mengatur pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Suku
Dayak Kenyah4. Cara penetapan hukuman Melalui pertemuan yang dihadiri oleh BPHTOS, yang terdiri dari
pemimpin adat, kepala desa dan masyarakat.
116JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
yang mengeluarkan keputusan, ijin memanfaatkankayu dan sangsi bagi yang melanggar. Pada saatpenelitian, hukum adat tersebut telah ditulis (Tabel2), namun demikian keputusan diambil biasanyamelalui musyawarah secara adat.
Keberadaan Desa Setulang diawali ketika OrangDayak Kenyah dari Sungai Pujungan memutuskanpindah ke daerah sekitar Sungai Setulang. Desa disekitar Sungai Setulang sepakat untuk memberimereka Hutan Setulang untuk menggantikan hutanadat mereka sebelumnya di Sungai Pujungan.Hutan dimaksud dikelola dan digunakan olehkeluarga bangsawan dan rekan-rekan mereka(Eghenter, 2000). Pemimpin adat pada saat itumemiliki kekuatan yang dominan dalam prosespengambilan keputusan tentang hutan.
Namun demikian, kekuatan dominan ituberakhir ketika pemerintah pusat mengeluarkanUU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Padatahun 1989, orang non-aristokrat pertama kalimenjadi kepala desa dan ia memerintah selamasepuluh tahun. Namun demikian, kekuasaan kepaladesa ini sering ditantang karena ia tidak berasal darikeluarga aristokrat. Awal pelaksanaan suksesi itutidaklah berjalan mulus seperti yang diharapkan.
Sementara itu, perubahan politik lokal telahmempengaruhi pengelolaan Hutan Setulang.Sekarang masyarakat biasa dapat berpartisipasidalam pengelolaan hutan dan mereka memilikipeluang lebih besar untuk menggunakan hutandengan izin dari BPHTOS.
Larangan berdasarkan Hukum Adat Setulangmeliputi pemotongan dan penggergajian kayu dihutan. Juga larangan perusahaan penebangan kayudan peraturan terhadap perluasan kebun dalamhutan ada. Aturan ini juga menegaskan bahwaMasyarakat Setulang tidak akan membiarkaneksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan wilayahadat mereka.
Hutan Setulang memiliki peranan yang pentingbagi kehidupan penduduk setempat. Bagi anak-anak dan remaja, hutan adat adalah tempat untukrekreasi, berenang dan berkemah selama musimliburan sekolah. Bagi wanita dewasa, hutan adalahsumber air, makanan dan kayu bakar untukkeperluan rumah tangga. Masyarakat jugadibolehkan berburu babi hutan dan menggunakankayu untuk membuat perahu panjang danmembangun rumah.
1. Pengelolaan hutan yang lebih demokratis
2. Konflik dengan perusahaan kayuGerakan untuk melindungi Hutan Setulang
semakin kuat di awal periode desentralisasi.Beberapa perusahaaan kayu datang danmenawarkan kerjasama untuk mengeksploitasiHutan Setulang. Beberapa Penduduk Senior DayakKenyah yang pernah mengalami bekerja diMalaysia, telah melihat kondisi rusaknya hutanyang telah ditebang dan tidak melihat manfaatyang nyata bagi penduduk desa-desa sekitar hutan.Perspektif untuk mempertahankan HutanSetulang mendapat dukungan dari
(CIFOR). Setelahbeberapa diskusi hangat, penduduk desamemutuskan untuk menjaga hutan mereka.Akibatnya, konflik langsung dengan perusahaankayu tidak bisa dihindari.
Sebenarnya, konflik di Kalimantan telah terjadisejak tahun 1970-an, terutama setelah pemerintahpusat mengizinkan perusahaan swasta untukberinvestasi dalam penebangan pada 1970-an.Reformasi di Indonesia yang diikuti desentralisasipada tahun 2001 diikuti dengan dengan makinmeningkatnya upaya untuk menegaskan kontrolatas tanah (Anau 2002). Beberapa kelompoksuku mengklaim hutan adat dan memutuskanuntuk menjualnya kepada perusahaan penebangan.
Desa Setulang juga menerima tawaran dariperusahaan kayu saat itu dan beberapa OrangSetulang yang mendukung pembangunan hampirberhasil menjual hutan. Mereka ditawarkan sekitarRp. 30.000-75.000 per meter kubik kayu (Kompas,2003). Pada tahun 1974, dua perusahaan kayuberoperasi di dekat Hutan Setulang: PT. Trang JayaNugraha di Setarap dan PT. Sanjung Makmur diSentaban. Kegia tan kedua per usahaanmenyebabkan air di Sungai Setulang menjadikeruh. Masuknya perusahaan kayu berarti desaharus mencari hutan pengganti untuk bahanbangunan mereka. Akhirnya Masyarakat Setulangmenolak ker jasama dari pengusaha IjinPemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK), yangdatang menjanjikan segala macam bantuan.
Selama awal desentralisasi tahun (2000-2002)delapan perusahaan kayu datang ke Desa Setulangresmi menawarkan usaha patungan denganmasyarakat setempat untuk penebangan kayu diHulu Sungai Setulang. Kadang MasyarakatSetulang harus berurusan dengan polisi sebagaikonsekuensi dari penolakan.
Center forInternational Forestry Research
et.al.,
117Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
Pada saat penelitian lapangan dilakukan, HutanSetulang masih tetap memiliki kondisi yang baik.Dalam prosesnya Penduduk Setulang sempatmendapatkan Kalpataru pada tahun 2003 yangdiserahkan oleh Presiden RI.
Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihakyang terkait dengan hukum adat dan pengamatan diDesa Setulang dan Desa Sesaot dan pengumpulandokumen dan data statistik, terdapat lima faktoryang berpengaruh terhadap pemberlakukan hukumadat di dalam pengelolaan hutan. Lima faktortersebut adalah: kohesivitas, hubungankekerabatan yang dekat, adanya dukungan dariberbagai pihak, kejelasan hak atas hutan,transparansi dan akuntabilitas khususnya keuangan.
Kohesivitas merupakan komponen pentingdalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Sebuahstudi di Amazon juga telah mengidentifikasi halyang sama (Schwartzman, dan Zimmerman, 2005).Diantara kasus Desa Sesaot dan Desa Setulang,Masyarakat Setulang menunjukkan adanyakohesivitas yang lebih memadai, sehingga merekaberhasil mencapai kesepakatan untuk memper-tahankan Hutan Setulang (lihat Bagian C2. Konflikdengan Perusahaan Kayu). Kepentingan yangberbeda antara orang-orang muda dan tua atauantara bangsawan dan rakyat biasa serta antarakebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkunganberhasil diakomodasi dalam satu kesepakatan.Terkait hal ini, orang dayak Kenyah memangmemegang tradisi untuk mewariskan hutan kepadagenerasi mendatang.
Masyarakat Sesaot, awalnya dapat mencapaikesepakatan mengaplikasikan dalampengelolaan agroforestri dan perlindungan hutan.Namun berangsur-angsur menjadi lemah seiringdengan protes dari masyarakat yang merasadirugikan, karena melanggar . Sementaraitu, dukungan instistusi melemah karena merasatugas pokok dan fungsi perlindungan hutan yangseharusnya menjadi tugas mereka telah tergantikanoleh masyarakat dengan hukum nya(Lihat Bagian B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan Sesaot)
Masyarakat adat telah memanfaatkan hubungan
D. Faktor yang Mempengaruhi
1. Kohesivitas
2. Hubungan kekerabatan
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Awiq-awiqAwiq-Awiq
kekerabatan dalam pemberlakukan hukum adatuntuk pengelolaan dan perlindungan hutan.Hubungan kekerabatan di Indonesia seringmemegang peranan penting dalam mengaksesinformasi. Masyarakat Setulang mempertahankanhubungan dekat dengan pejabat KabupatenMalinau (Wollenberg, 2006). Pada saat penelitiandilakukan, Marthin Billa (Bupati Malinau) adalahOrang Dayak Kenyah yang lahir di Apo Kayan danmemiliki beberapa kerabat yang tinggal di DesaSetulang. Latar belakang etnis memastikanhubungan yang erat antara Bupati dan DesaSetulang. Hubungan dekat ini juga didukung olehfakta bahwa beberapa orang yang bekerja tetap atautidak tetap di kantor kabupaten dan di kantorlembaga donor seperti CIFOR-Malinau jugakerabat dari Desa Setulang. Kekerabatan inimembuat Orang Setulang dapat lebih mudahmengakses informasi dan melakukan konsultasitentang pendanaan dan proyek-proyek pem-bangunan dari Pemerintah. Hubungan erat antarapemerintah kabupaten dan masyarakat Setulangjuga menyebabkan daya tawar yang lebih dalamberurusan dengan pengelolaan Hutan Setulang danpelaksanaan kegiatan adat.
Pada kasus Masyarakat Sasak di Sesaot, jelassekali terlihat kurangnya ikatan kekerabatan antaramasyarakat dengan para pejabat di pemerintahandaerah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, parapejabat Pemda Tingkat I dan II berasal dari sukuyang beragam, misalnya Sasak, Sumbawa dan Jawa.Akibatnya rasa keterikatan dengan adat ( )juga kurang kuat, karena perbedaan suku dankebiasaan.
Dukungan para pihak dalam pemberlakukanadat dalam pengelolaan hutan merupakan hal yangsangat penting. Masyarakat Setulang mendapatdukungan kuat dari sebuah lembaga penelitianinternasional, seperti CIFOR. Dukungantermasuk dalam bentuk dana dan pembangunanfasilitas rekreasi (Lihat Bagian C2. Konflik denganPerusahaan Kayu ).
Di lain pihak, pelaksanaan di Sesaotpada awalnya juga didukung banyak pihak (LihatBagian B. dalam Mengelola danMelindungi Hutan Sesaot). Namun demikian,KMPH yang mempelopori akhirnyakehilangan dukungan dari masyarakat danpemerintah provinsi. Lebih lebih setelah pengelola
Awiq-awiq
Awiq-awiq
Awiq-Awiq
Awiq-awiq
3. Dukungan berbagai pihak
118JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
Hutan Sesaot berubah dari pemerintah provinsimenjadi pemerintah kabupaten. Hilangnyadukungan dana, akses informasi dan keberadaanhukum adat, otomatis memperlemah pember-lakukan hukum adat, .
Permasalahan ketidakkejelasan hak masyarakatlokal dalam pengelolaan hutan di Indonesiamemang bukan hal baru. Konflik-konflik lahanhutan sering terdengar di berbagai tempat. Hal yangsama terjadi di Desa Sesaot dan Desa Setulang.
Berbeda dengan Hutan Sesaot yang sejak awaltelah dieksploitasi oleh pengusaha kayu, HutanSetulang belum dieksplotasi dan secara historismerupakan warisan para leluhur Orang Setulang.Hal ini menjelaskan mengapa Masyarakat Setulanglebih gigih menuntut hak kepemilikan danpengelolaan terhadap Hutan Setulang. OrangSetulang juga memiliki kekawatiran akan kelestarianHutan Setulang.
Masyarakat Setulang khawatir bahwa suatu saatpemerintah daerah (kecamatan dan kabupaten)akan membuat keputusan tentang pemanfaatanhutan adat mereka tanpa mengikutsertakanMasyarakat Setulang dalam proses pengambilankeputusan (komunikasi dengan tokoh DesaSetulang). Mereka kawatir bahwa akan terjadipembangunan perkebunan kelapa sawit ataupenebangan pohon di wilayah hutan adat mereka,sebagaimana banyak terjadi disekitar mereka.Kurangnya kejelasan hak kepemilikan lahan iniberpotens i menjadi penghambat usahapemberlakukan hukum adat untuk melindungi danmengelola Hutan Setulang.
Transparansi dan akuntabilitas merupakankomponen yang juga tak kalah penting dalam tatakelola hutan yang baik. Tidak itu saja, faktor initernyata juga penting dalam proses pemberlakuanperaturan adat dalam pengelolaan danperlindungan hutan.
Bagi masyarakat Setulang, transparansi danakuntabilitas adalah hal yang seharusnya dilakukanpara pihak terkait (komunikasi dengan seorangtokoh di Desa Setulang). Pembelajaran mengenaiakibat dari ketidaktransparanan dan kurangnyaakuntabilitas didapat dari pengalaman masyarakatdi sekitar mereka. Dalam sebuah kasus, Inhutani II,sebuah perusahaan kayu milik negara, dituntutuntuk membayar 50 miliar rupiah terhadap tuntutan
Awiq-awiq
4. Kejelasan hak kepemilikan lahan hutan
5. Transparansi dan akuntabilitas
masyarakat yang hutan adatnya ditebang. Setelahnegosiasi tuntutan dikurangi menjadi 2,5 miliarrupiah. Inhutani II membayar 2,5 miliar rupiahuntuk sekitar 50 rumah tangga. Setiap rumahtangga seharusnya mendapatkan 400 juta rupiah,tapi akhirnya, masing-masing hanya menerimasekitar 200 ribu rupiah. Sebuah hasil penelitian ditiga desa di Kabupaten Malinau menemukanbahwa hampir 50 persen responden merasa bahwaekonomi mereka telah menurun setelahperusahaan penebangan skala kecil (IPPK)beroperasi dibandingkan sebelum masuknya IPPK(Affandi, 2006).
Penelitian ini menemukan bahwa hukum adatmerupakan bagian dari kehidupan sebagianmasyarakat Indonesia. Hukum adat memilikipotensi untuk mengelola dan melindungi hutansecara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutansecara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnyadilakukan melalui musyawarah. danhukum adat Orang Setulang (Suku Dayak Kenyah)sama-sama efektif untuk melindungi hutan,namun seiring berjalan waktukehilangan dukungan dari pemerintah dansebagian masyarakat setempat. Karena itu, perludiperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhipemberlakukan hukum adat dalam pengelolaandan perlindungan hutan yaitu kohesivitas,dukungan pihak terkait yaitu pemerintah, LSM dandonor, ikatan kekerabatan, kejelasan hak atashutan, tranparansi dan akuntabilitas, khususnyadalam bidang keuangan.
Mengingat pentingnya hukum adat, penelitianini menyarankan kepada pihak-pihak terkait yaitupemerintah, LSM, akademisi dan donor: pertama,dilakukan pemetaan dan inventarisasi masyarakatlokal yang mengaplikasikan hukum adat dalampengelolaan dan perlindungan hutan. Kedua,pemerintah segera menyelesaikan dan mensahkanRUU tentang hutan adat; ketiga, pemerintahseharusnya memberikan dukungan dan insentifkepada masyarakat adat Desa Sesaot dan Setulangdalam usahanya melindungi hutan. Terakhir,pentingnya meningkatkan kolaborasi masyarakatlokal dengan Pemda dalam mempertahankanwarisan hukum adat. Dalam hal ini, Pemda dapatmemberi dukungan dana dan memfasilitasi
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Awiq-awiq
Awiq-awiq
119Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
pembinaan terhadap masyarakat adat. Sementaraitu, untuk membenahi transparansi danakuntabilitas keuangan yang berkaitan denganpengelolaan dan perlindungan hutan dapatdilakukan dengan cara membuat laporan danevaluasi secara berkala yang diinformasikan kepadasemua pihak terkait. Bahkan penting pula dilakukanaudit jika memang diperlukan.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Colin Filer, Dr. David Lawrence, Dr. Lesley Potterdan Dr. Budy Resosudarmo dari AustralianNational University serta Profesor CaruniaFirdausy dari LIPI yang telah memberi bimbingandan masukan selama melakukan penelitian ataupenulisan.
Acciaioli, G. 2006. Environmentality Reconsidered:Indigenous to Lore Lindu ConservationStrategies and the Reclaiming of theCommons in Central Sulawesi, Indonesia.Dalam: Anonim (Ed). Survival of theCommons: Mounting Challenges and NewRealities," the Eleventh Conference of theInternational Association for the Study ofCommon Property . Bali, 19-23 June. IndianaUniversity: Digital Library of Commons.
Affandi, O. 2006. The Impact of IPPK andIUPHHK on Community Economies inMalinau District. Governance Brief (May2006): 1-5.
Apomfires, F.F. 1998. Perubahan Institusi Adat danKerusakan Hutan Kasus pada MasyarakatAdat Sentani, Irian Jaya. Tesis Magister.Universitas Indonesia. Jakarta. 195 halaman.
Anau, N., R. Iwan, M. van Heist, G. Limberg, M.Sudana and E. Wollenbergh. 2002. TechnicalReport Phase I 1997-2001:ITTO Project Pd12/97 Rev.1. Bogor:Centre for InternationalForestry Research (CIFOR).
Assambe-Mvondo, 2010. The Customary LawNature of Sustainable Forest managementStatesPractice in Central America and
Ucapan terima kasih
DAFTAR PUSTAKA
European Union. Forest Ecology andManagement 3(2):58-70.
Ayuthaya, P.N.N., 1996. Community Forestry andWatershed Networks in Northern Thailand.Prosiding Seeing Forests for Trees:Environment and Environmentalism inThailand. Chiang Mai. Silkworm Books.
Badan Pusat Satistik Indonesia, Sensus PendudukTahun 2000.
Badan Pusat Satistik Indonesia , Survey PotensialDesa 2005.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, 2006.Kecamatan Malinau Selatan Dalam Angka2004. Malinau. Malinau: Badan PusatStatistik Kabupaten Malinau.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat,2003. Narmada dalam Angka. Narmada:Badan Pusat Statistik Kabupaten LombokBarat.
Contreras-Hermosilla, A. and C. Fay, 2005.Strengthening Forest Management inIndonesia through Land Tenure Reform:Issues and Framework. Bogor: ForestTrends.
Departement Van Economische Zaken, 1935.Census of 1930 in the Netherlands Indies:Volume IV, Native Population in Sumatera.Batavia: Departement Van EconomischeZaken.
Eghenter, C., 2000. What Is Tana Ulen Good For?Considerations on Indigeneous ForestManagement, Conservation, and Researchin the Interior of Indonesian Borneo.Human Ecology 28(3): 331-357.
Gautama, I. 2008. Studi Komplain KepemilikanHutan Adat Masyarakat di Daerah AliranSungai Kabupaten Luwu Timur.9(2):96-104.
ICRAF (World Agroforestry Centre) dan KPSHK(Konsorsium Pendukung Sistem HutanKerakyatan), 2001. Inisiatif dan KebijakanYang Berhubungan dengan Hak-HakMasyarakat Adat: Kedai III DiselenggarakanBersama oleh ICRAF dan KPSHK,Crawford Lodge, Bogor, 21 November 2000Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF,
J.Agrisains
120JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 110 - 121
SEA Regional Office.
), diakses 27Januari 2008.
ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK(Konsorsium Pendukung Sistem HutanKerakyatan) and JKPP (Jaringan KerjaPemetaan Partisipatif), 2001. KelembagaanMasyarakat Adat dalam Mengelola SumberDaya Hutan: Kedai II DiselenggarakanBersama Oleh ICRAF, KPSHK, dan JKPP,Crawford Lodge, Bogor, September 2000.Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF,SEA Regional Office. (
/ sea/Publications/ files/book/BK0023-04.PDF),diakses 27 Januari 2008.
Kementerian Kehutanan, 1997. Peta VegetasiIndonesia.
. Diakses 18 Februari 2013.
Kementerian Kehutanan, 2011. trategisKehutanan 2012. Jakarta: KementerianKehutanan.
KMPH (Kelompok Mitra Pelestari Hutan) Sesaot,2000 . Proposa l Per mohonan HakPengelolaan Hutan Kemasyarakatan: KMPHSesaot, Desa Batu Mekar, Sesaot, LebahSempage dan Sedau. Mataram: KMPH.
Kompas, 2003. Warga Setulang MenolakPenebangan Hutan Adat. , 3November
Mulyoutami, E, R. Rismawan, L. Joshi , 2009. Localknowledge and management of Simpukng(forest gardens) among the Dayak people inEast Kalimantan, Indonesia. Forest Ecologyand Management 257(2009): 2054-2061.
Schwartzman, S. dan B. Zimmerman, 2005.Conservation Alliances with IndigeneousPeople of the Amazon. ConservationBiology 19(3): 721-727.
http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/files/book/BK0021-04.PDF
http://www.wor ldag rofores t r ycent re.org
http://www.dephut.go.id/Halaman/Peta%20Tematik/PL&Veg/veg_97/vgindo.gif
Data S
Kompas.
Sembiring, S. and E. Effendi (eds), 1999. KajianHukum dan Kebijakan PengelolaanKawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta:Indonesian Center for Environmental Law.
Sidiyasa, K., Zakaria and I. Ramses, 2006. TheForest of Setulang and Sengayan in MalinauEast Kalimantan. Bogor. Centre forInternational Forestry Research (CIFOR).
Suryadi, S., 1998. Partnership Association forForest Protection and Management:Breaking Ground for Community-BasedManagement in the Sesaot Protected ForestArea Crossing Boundaries, the SeventhAnnual Conference of the InternationalAssociation for the Study of CommonProperty. Vancouver,British Columbia,Canada, 10-14 June: Indiana University:Digital Library of Commons.
Suryadi, 2001. Enabling Policy Frameworks forSuccessful Community Based ResourceManagement Initiatives. Dalam K.Suryanata, G. Dolcemascolo, R. Fisher andJ.Fox (eds) Prosiding Eighth Workshop onCommunity Management of Forest Land.Hawai: East West Center and RegionalForestry Training Center.
Sutedjo, E.B dan Suryadi, 1997. Government andNGO Collaboration in Social ForestryDevelopment in Protected Areas: A CaseStudy from Sesaot, West Lombok,Indonesia. Dalam M. Victor, C. Lang and J.Bornemeir (eds).Community Forestry atCrossroads: Reflections and FutureDirections in the Development ofCommunity Forestry, Vol. 16. Bangkok:RECOFT.
Wollenberg, E., M. Moeliono, G. Limberg, I. R, S.Rhee and M. Sudana, 2006. Between Stateand Society: Local Governance of Forest inMalinau, Indonesia. Forest Policy andEconomics 2006(8): 421-433.
121Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan ..... Magdalena( )
PENGARUH DINAMIKA SPASIAL SOSIAL EKONOMI PADASUATU LANSKAP DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERHADAP
KEBERADAAN LANSKAP HUTAN (STUDI KASUS PADADAS CITANDUY HULU DAN DAS CISEEL, JAWA BARAT)(
)
Effect of Spatial Dynamics of Socio-Economic in the WatershedLandscape Toward The Existence of the Forest Landscape;
Case Studies on Citanduy Hulu Watershed and Ciseel Watershed,West Java
1 2
1
2
Edy Junaidi, Retno MaryaniBalai Penelitian Kehutanan Ciamis, Jalan Ciamis-Banjar Km. 4 P.O. Box 5. Telp. 0265771352
email: [email protected] Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunung Batu No.5 Bogor PO Box 272 Bogor 16167
iterima 22 Januari 2013, direvisi 10 Mei 2013, disetujui 17 Mei 2013
Kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat ekologis,ekonomis maupun sosial. Pengelolaan sumberdaya hutan perlu dilakukan dengan berorientasi ekosistem secarakeseluruhan. Oleh karenanya, rencana penataan tata guna hutan perlu pengelolaan di tingkat lanskap. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui adanya hubungan timbal balik antara kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada didalam wilayah suatu DAS dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi terjadinya dinamika lanskap hutan.Metode untuk menentukan keeratan masing-masing karakteristik (lingkungan dan sosial-ekonomi) dengankeberadaan hutan, menggunakan model (GWR) dengan melihat nilai korelasinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor biofisik dan sosial ekonomi yang mempunyai korelasi yang kuat terhadapkeberadaan lanskap hutan pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel adalah (i) curah hujan, (ii) kelerengan, (iii)kepekaan tanah terhadap erosi, (iv) kerapatan drainase, (v) rata-rata lereng, (vi) kepadatan agraris dan (vii)ketegantungan terhadap lahan.
Kata kunci: Biofisik, sosial ekonomi dan lanskap hutan
D
ABSTRACT
Forest sustainability can not be separated from its surrounding environment, both ecological, economic and social. Management offorest resources that need to be done must be oriented toward ecosystem in totality. Therefore, the arrangement of land use forest plan needmanagement at a landscape level. This study aims to investigate the interrelationship between socio-economic conditions of the peopleresiding at watershed and environmental conditions that affect dynamics of forest landscape. The method for determining closeness of eachcharacteristic (environmental and socio-economic) with the forest existence, uses Geographically Weighted Regression models (GWR), bylooking at value of the correlation. Results showed that biophysical and socio-economic factors that have a strong correlation towardexistence of the forest landscape in the Citanduy Hulu Watershed and the watershed Ciseel were: (i) rainfall, (ii) slope, (iii) erosion soilsensitivity, (iv) drainage density, (v) average slope, (vi) density and (vii) dependence on agricultural land.
Keywords: Biophysical, social-economic and forest lansdcape
Geographically Weighted Regression
ABSTRAK
I. PENDAHULUAN
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) mem-berikan arahan spasial pengelolaan lahan yangditetapkan sebagai kawasan hutan. KementerianKehutanan telah menyusun arahan spasial kawasanhutan di dalam dokumen Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK) yang memperhatikan hasilRTRW. Pada dokumen TGHK ditetapkan wilayahspasial kawasan hutan dan pengelolaan kawasansesuai dengan fungsinya.
Pengelolaan hutan bertujuan untuk me-lestarikan sumberdaya hutan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya
122JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
masih terdapat masyarakat miskin di dalam dandisekitar hutan. Kemiskinan masyarakat ini didugamemicu proses deforestasi dan degradasi hutan.Kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan darikondisi lingkungan sekitarnya, baik yang bersifatekologis, ekonomis maupun sosial. Pengelolaansumberdaya hutan perlu dilakukan denganberorientasi ekosistem secara keseluruhan. Olehkarenanya, rencana tata guna hutan perlu dilakukandi tingkat lanskap.
Salah satu definisi lanskap dikemukakan Green(1996). Lanskap merupakan konfigurasi khusus
dari topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahandan pola pemukiman yang membatasi proses-proses alam dan budaya. Lanskap hutan dicirikanoleh karakteristiknya sebagai bentang alam yangdidominasi oleh adanya faktor biotik hutan yangwilayahnya terdapat di pegunungan dan pantai.Lanskap hutan merupakan bentang alam yangdidominasi oleh adanya hutan yang wilayahnyameliputi dari daerah hulu hingga ke bagian hilir.Lanskap hutan dapat dibatasi oleh suatu wilayahekologi. Wilayah ekologi yang sering dipakai sebagaibatas adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). LanskapDAS yang lebih komplek daripada lanskap hutanyang merupakan interaksi antara struktur penyusundan fungsinya, menjadi alasan sebagai basis kajianlanskap hutan.
Pengelola hutan di Indonesia melalui pen-dekatan klasik mengklasifikasikan hutan sesuaidengan fungsinya, yaitu sebagai hutan produksi,hutan konservasi dan hutan lindung. Peng-klasifikasian fungsi hutan ini hanya berdasarkankondisi ekologis saja yaitu ketinggian tempat,kelerengan, jenis tanah dan curah hujan.Pendekatan pengelolaan semacam ini kurang tepatkarena masih terjadi proses degradasi dandeforestasi hutan. Pendekatan pengelolaan ini dapatdilakukan perbaikan dengan menerapkanmanajemen lanskap hutan yang memandang hutansebagai suatu kesatuan fungsi, dan pengelolaannyatidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk memenuhikebutuhan yang beragam.
Manajemen lanskap hutan dapat menunjukkanagar proses perubahan yang dibentuk dandipengaruhi kondisi hutan dalam skala luas dandalam waktu yang panjang dapat dipahami olehperencana pembangunan. Kajian lanskap hutanmencakup sebaran luas dan tutupan hutan sertasebaran fungsi hutan dan perubahannya, yangdiakibatkan oleh adanya dinamika sosial-ekonomi
etal.
dalam tataran spasial serta adanya dinamikalingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiadanya hubungan timbal balik antara kondisi sosialekonomi masyarakat yang berada di dalam wilayahsuatu DAS dengan kondisi lingkungan yangmempengaruhi terjadinya dinamika lanskap hutan.Manfaat yang akan dihasilkan dari adanyapenelitian ini adalah diperolehnya informasikondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkunganyang mempengaruhi keberadaan hutan baik luasdan fungsinya, sebagai dasar bagi pengambilkebijakan untuk merumuskan regulasi pengelolaanhutan
Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) sub DASyang berada di wilayah DAS Citanduy, yaitu subDAS Citanduy Hulu dan sub DAS Ciseel. Untukposisi administrasi dan posisi geografis lokasipenelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Sub DASCitanduy Hulu berada pada hulu DAS Citanduyyang memiliki karakteristik dengan kepadatanpenduduk tinggi dan tekanan terhadap lahan yangberat, sedangkan DAS Ciseel berada pada bagianhilirDAS Citanduy yang memiliki karakteristikkepadatan penduduk sedang dengan tekananterhadap lahan yang rendah.
Tahapan kegiatan penelitian dibedakan menjadi3 (tiga), yaitu tahapan survei, tahapanpengelompokan data dan tahapan analisa data.Kegiatan pada masing-masing tahapan sebagaiberikut :1. Kegiatan Survei
Kegiatan survei terdiri dari beberapa tahapanyang dibedakan sebagai berikut:
a. PersiapanKegiatan persiapan berupa kegiatan
pengumpulan data sekunder yang dilakukanmelalui studi pustaka yang meliputi laporan-laporan dan peta-peta dari instansi-instansiterkait. Jenis data yang dikumpulkan berupadata meteorologi (curah hujan, temperatur,radiasi matahari dan kecepatan angin), dataSPAS (Stasiun Pengamatan Arus Sungai), data
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
B. Metode Penelitian
.
123Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
karakteristik lahan, data karakteristik tanah, datasosial - ekonomi, peta administrasi terbaru, petatanah terbaru, peta penggunaan lahan (tahun2003, 2006 dan 2009), peta TGHK dan petaRTRW Kabupaten (Garut, Ciamis danTasikmalaya).b. Inventarisasi
Pada kegiatan ini dilakukan survei dandi lapangan untuk mengumpulkan data
primer pada lokasi sampel menggunakanpendekatan unit lahan. Penyusunan unit lahandilakukan dengan cara membagi setiap sub-subDAS ke dalam satuan peta yang mempunyaikesamaan parameter penggunaan lahan, lereng,curah hujan tahunan dan jenis tanah. Sampelpewakil ditentukan dengan caramembuat garistransek pada beberapa sub-sub DAS dimanagaris tersebut dapat memotong sebagianterbesar dari unit lahan yang ada.c. Pengelompokan data hasil persiapan daninventarisasi
Data hasil kegiatan persiapan daninventarisasi selanjutnya ditabulasi dalam bentuktabel sesuai dengan kelompok karakteristik(lingkungan dan sosial-ekonomi) sebagimanaditunjukkan pada Tabel 1. Masing-masingkelompok data tersebut dibuatmenggunakan kriteria yang telah ada (Arsyad
groundcheck
skoring
(2006), Paimin (2006), Kepres No. 32 danSK Mentan No. 837) (Lampiran 1). Kemudiandibuat peta sebaran spasial (peta tematik) yangakan digunakan pada tahapan analisis.
Untuk menentukan keeratan masing-masingkarakteristik (lingkungan dan sosial-ekonomi)dengan keberadaan hutan, digunakan model
(GWR). Tingkatkeeratan antara masing-masing karakteristikdengan keberadaan hutan ditentukan berdasarkanbesarnya koefisien korelasi (r). Makin tingginilai korelasinya berarti hubungan masing-masing karakteristik dengan keberadaan hutanmakin erat.
Persamaan umum GWR yang dikembangkanoleh Fotheringham .(2002) adalah
y = a (u ,v (u ,v
di mana y adalah variabel bebas (luas hutan), a dana adalah variabel tak bebas berupa karakteristiklingkungan dan sosial-ekonomi, adalah nilai erorpersamaan dan (u ,v )adalah koordinat masing-masing variabel. Perhitungan model GWRdilakukanmenggunakan bantuan software statistikspasial SAM 4.
et. al.
Geographically Weighted Regression
et. al
C. Analisis Data
i 0 i i k i i i
i 0
k
i
i i
) + Σk a ) xik + ε
ε
124
Gambar 1. Lokasi penelitian DAS Citanduy Hulu dan DAS CiseelFigure 1. Study location at Citanduy Hulu Watershed and Ciseel Watershed
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Biofisik
1. DAS Citanduy HuluDAS Citanduy Hulu terletak pada hulu DAS
Citanduy yang secara geografi terletak pada 7 7' - 717' LS dan 108 4' - 108 24' BT. Luas DAS CitanduyHulu sekitar 72.409,5 ha. Panjang rata-rata sungaiutama sekitar 7,4 km dengan gradien 1,02 % (agakrendah).
Pada penelitian ini DAS Citanduy Hulu dibagimenjadi 67 sub DAS. Pembagian ini dimaksudkanuntuk mempermudah melakukan analisis lebihlanjut. Karakteristik masing-masing sub DAS dapatdilihat pada Lampiran 2.
Berdasarkan citra Landsat TM tahun 2009terdapat 9 penggunaan lahan pada DAS CitanduyHulu, yaitu belukar, hutan, pemukiman, pertaniansemak, sawah, tambak, tubuh air, pertanian danrawa. Luas masing-masing penggunaan lahan dapat
o o
o o
dilihat pada Tabel 2, sedangkan letak penggunaanlahan secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2
Luasan penggunan lahan di DAS Citanduy Huluyang berhutan sekitar 20,73 %, pertanian semaksekitar 25,61 %, pertanian (pertanian dan sawah)sekitar 67,23 %, pemukiman sekitar 10,68 % danpenggunaan lahan (belukar, tambak, tubuh air danrawa) sekitar 1,36 % dari total luas DAS.
a. Keadaan iklimPeta sebaran spasial curah hujan tahunan selama
5 (lima) tahun yang berasal dari 6 (enam) stasiuncurah hujan (stasiun curah hujan Kadipaten,Panjalu, Pagerageung, Ciamis, Cihonje danTasikmalaya) yang tersebar pada DAS CitanduyHulu dapat dilihat pada Gambar 3A.
Berdasarkan Gambar 3 (A) dapat diketahuibahwa sebagian besar wilayah DAS Citanduy Huluberada pada kisaran curah hujan lebih dari 2000mm/tahun, yakni termasuk dalam kriteria tinggi,sedangkan luas wilayah DAS yang berada pada
.
125
No.Karakteristik( haracteristic)C
Kelompok Data(Data group)
Jenis Data(Data type)
Teknik Inventarisasi(Inventory techniques)
1 Biofisik Iklim Curah hujan tahunan (mm) - Data hujan di DASHujan rata-rata harian maksimum(mm/hari)
- Data hujan 5 – 10 tahun terakhir
Evapotranspirasi aktual tahunan (mm) - Data iklim di DAS- Metode perhitungan evapotranspirasi
Lahan Kelerengan lahan (%) - Peta topografi- Program GIS
Bentuk lahan - Peta geomorfologiTanah Kedalaman solum tanah (mm) - Survei lahan
Batuan singkapan (%) - Survei lahanDrainase tanah - Survei lahanPermiabilitas ( - Hasil analisa tanahErodibitas tanah - Hasil analisa tanahHidrologi tanah - Hasil analisa tanah
Morfometri DAS Bentuk DAS - Peta DASGradien sungai (%) - Menggunakan metode Benson (1962)
α = (h85 – h 10) (0,75 LB)Ket : LB = panjang sungai
h = elevasiKerapatan drainase (km/km2) - Rumus Dd = L/A
Ket : L = panjang sungaiA = luas DAS
Lereng rata-rata DAS (%) - Peta topografi- Program GIS
Geologi Jenis batuan - Peta geologi2 Sosial - ekonomi Sosial Rasio penduduk - Data BPS
Kepadatan penduduk geografis (orang/ha) - Data BPSKepadatan agraris (orang.ha) - Data BPSTenaga kerja produktif - Data BPSPengelompokan tenaga kerja - Data BPS
Ekonomi Ketergantungan terhadap lahan (%) - Data BPSTingkat pendapatan - Data BPSKegiatan dasar wilayah (LC) - Data BPS
Tabel 1. Kelompok masing-masing data pada tiap-tiap karakteristikTable 1. Each group of data on each characteristic
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
126
Tabel 2. Luas masing-masing penggunaan lahan di DAS Citanduy Hulu2.Table Area of each land use in Citanduy Hulu watershed
NoPenggunaan Lahan
(Land use)Luas (Ha)
(Area)Persentase (%)
(Prosentage)
1 Belukar 553.8 0.762 Hutan poduksi 887.9 1.233 Hutan terbatas 4,974.3 6.874 Hutan lindung 9,146.7 12.635 Pemukiman 7,730.3 10.686 Pertanian semak 18,543.3 25.617 Sawah 20,676.1 28.558 Tambak 12.7 0.029 Tubuh air 420.5 0.58
10 Pertanian 9,462.5 13.0711 Rawa 1.3 0.00
T o t a l 72,409.5 100
Gambar 2. Peta sebaran spasial penggunaan lahan di DAS Citanduy Hulu2. sFigure Map of patial distribution land use in Citanduy Hulu watershed
kisaran curah hujan kurang dari 2000 mm/tahunhanya sekitar 12 % dari luas DAS, tepatnya hanyadisekitar hilir DAS Citanduy Hulu.
Gambar 3 (B) menunjukkan peta sebaran nilaievapotranspirasi aktual pada DAS Citanduy Huluyang dihitung menggunakan metode Thornthwaitedari 4 (empat) stasiun iklim yang berada disekitarDAS Citanduy. Berdasarkan gambar tersebutdiketahui bahwa sebagian besar DAS Citanduy
Hulu berada pada nilai aktual evapotranspirasilebih dari 1000 mm/tahun, yakni termasuk kriteriasedang.
b. Keadaan geologi dan jenis tanahBerdasarkan Peta Geologi, jenis batuan induk
(geologi) yang terdapat di DAS Citanduy Hulusebagian besar didominasi oleh campuran antarabatuan andesit, basalt dan tefra berbutir halus (68
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
127
Gambar 3. (A) Peta sebaran spasial curah hujan tahunan DAS Citanduy Hulu; (B) Peta sebaran spasialevapotranspirasi aktual tahunan DAS Citanduy Hulu
Figure 3. (A) Map spatial distribution of annual rainfall in Citanduy Hulu watershed; (B) Map spatial distribution ofannual actual evapotranspiration in Citanduy Hulu watershed
(A) (B)
Gambar 4. (A) Peta geologi pada DAS Citanduy Hulu; (B) Peta jenis tanah;Figure4. (B)Geological map of the Citanduy Hulu Watershed (B) Map soil types)
% luas DAS). Pada Gambar 4 (A) terlihat sebaranjenis batuan di DAS Citanduy Hulu. Jenis batuanandesit, basalt dan tefra berbutir halus hampirtersebar merata pada bagian tengah dan hilir DASCitanduy Hulu.
Terdapat 11 macam jenis tanah yang ada padaDAS Citanduy Hulu. Jenis tanah terluas sebarannyadidominasi oleh latosal coklat kemerahan (30 %)dan latosal coklat (16 %), dimana keduanya merupakan jenis tanah yang peka erosi.Sebaran spasialjenis tanah pada DAS Citanduy Hulu dapat dilihatpada Gambar 4 (B). Tanah-tanah yang kurang pekaerosi (jenis latosol) hampir mendominasi pada
-
tengah dan hilir DAS, sedangkan tanah-tanah yangkurang peka terhadap erosi (tanah jenis andosol)berada pada hulu DAS. Peta sebaran kedalamantanah, permiabilitas tanah, kandungan bahanorganik tanah, dan nilai kepeka an erosi tanah (nilaiK) dapat dilihat pada Gambar 5. (A, B, C dan D)
Pada Gambar 6 (A) terlihat sebagian besarwilayah DAS Citanduy berada pada ketinggian 250- 750 m dpl. Kisaran ketinggian ini hampirmenempati lebih 50 % luas DAS dan tersebarmerata pada wilayah tengah dan hilir DAS.
Pada DAS Citanduy hulu terdapat 5 (lima) kelaskelerengan, yaitu kelas 0 - 8 % (luas 40 % dari luas
-.
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
128
(A) (B)
(C) (D)
Gambar 5. Karakteristi masing-masing jenis tanah pada DAS Citanduy Hulu, (A) kedalaman horizon, (B)permiabilitas, (C) kandungan bahan organik dan (D) nilai kepekaan tanah terhadap erosi
Figure 5. Characteristic of each type of soil in the Citanduy Hulu Watershed, (A) depth of horizon, (B) permeability, (C)organic matter content and (D) the value of erosion soil sensitivity
Gambar 6. (A) Peta sebaran spasial ketinggian tempat pada DAS Citanduy Hulu; (B) Peta kemiringanlereng
(Figur 6. A) Map of elevation ofspatial distribution in the Citanduy Hulu watershed; (B)Map of slope
(A) (B)
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
DAS), kelas 8 - 15 % (22 % dari luas DAS), kelas15 - 25 % dengan luas 18 % dari luas DAS, kelas 25 -40 % mempunyai luas 15 % dari luas DAS dan kelas> 40 % dengan luas 5 % dari luas DAS (Gambar 6(B). Sebaran spasial kelerengan pada DAS CitanduyHulu dapat dilihat pada Gambar 6 (B), dimana kelaskelerengan 0 - 8 % tersebar pada DAS bagian tengahdan hilir, sedangkan kelas kelerengan yang lainterbesar merata pada hulu dan hilir DAS.
Letak DAS Ciseel secara geografis, yaitu pada 737' - 7 17' LS dan 108 24' BT. DAS Ciseel yangterletak pada DAS Citanduy bagian hilir,berdasarkan hasil analisa dengan bantuan GISmempunyai luas sekitar 61.905,1 Ha. Panjang rata-rata sungai utama DAS Ciseel sekitar 7,1 km dengangradien sungai agak rendah yakni 0,73 %.
Dengan menggunakan bantuan GIS, DAS Ciseeldalam penelitian ini dibagi menjadi 65 sub DASdengan tujuan untuk mempermudah dalammelakukan analisis. Karakteristik masing-masingsub DAS dapat dilihat pada Lampiran 3.
Pada DAS Ciseel luas penggunaan lahan hutan(25 % luas DAS) dan yang bertajuk kayu
2. DAS Ciseelo
o o
(perkebunan dan pertanian semak) lebih luasdibandingkan areal untuk pertanian (14 % luasDAS). Gambar 7 menunjukkan sebaran spasialpenggunaan lahan yang tersebar pada DAS Ciseel.
a. Keadaan iklimPeta sebaran spasial curah hujan tahunan
dianalisis berdasarkan data curah hujan selama 5(lima) tahun. Data curah hujan berasal dari 5 (lima)stasiun curah hujan yaitu stasiun curah hujanCineam, Pataruman, Sidamulih, Cikupa danCilacap yang tersebar pada DAS Ciseel.
Gambar 8 A menampilkan luasan danpersentase curah hujan pada wilayah DAS Ciseel.Pada peta terlihat bahwa sebagian besar wilayahDAS Ciseel berada pada kisaran curah hujan lebihbesar 2000 mm/tahun (kriteria tinggi), dimanaluasan wilayah tersebut meliputi 77 % dari luasDAS Ciseel, sedangkan sisanya merupakan wilayahDAS yang mempunyai curah hujan lebih kecil 2000mm/tahun, tepatnya disekitar hilir DAS Ciseel.
Wilayah DAS Ciseel berdasarkan klasifikasiiklim Mohr (1993) termasuk Golongan II yaknidaerah agak basah dan berdasarkan klasifikasi iklimSchmidt - Fergusson (1951) termasuk tipe hujangolongan B yakni basah.
129
Gambar 7. Peta sebaran spasial penggunaan lahan di DAS CiseelsFigure 7. Map of patial distribution land use in Ciseel watershed
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
Gambar 8 B menunjukkan peta sebaran nilaievapotranspirasi aktual pada DAS Ciseel denganmenggunakan metode Thornthwaite dari 4 (empat)stasiun iklim yang berada disekitar DAS Citanduy.Peta tersebut menunjukkan bahwa seluruh DASCiseel berada pada nilai aktual evapotranspirasilebih dari 1000 mm/tahun yakni termasuk kriteriasedang.
b. Keadaan geologi dan jenis tanahGambar 9 A menunjukkan sebaran spasial peta
geologi yang terdapat di DAS Ciseel. Berdasarkangambar tersebut diketahui bahwa sebagian besarjenis batuan induk pada DAS Ciseel didominasioleh endapan aluvial muda yang menempati 45 %
dari luas DAS, serta batuan induk yang berasal dariandesit, basalt dan brecia yang menempati luaswilayah DAS sekitar 32 %. Untuk jenis batuaninduk lain dapat dilihat pada Gambar 9 A.
Berdasarkan Gambar 9 A terlihat bahwa jenisbahan induk endapan aluvium tersebar meratapada bagian tengah dan hilir DAS Ciseel,sedangkanjenis batuan lain tersebar pada hulu DAS.
Terdapat 11 macam jenis tanah yang ada padaDAS Ciseel. Jenis tanah terluas sebarannyadidominasi oleh komplek podsolik merahkekuningan, podsolik kuning dan regosol (28 %)serta komplek regosol dan litosol (27 %). Jeniskomplek podsolik merah kekuningan, podsolik
130
Gambar 8. (A) Peta sebaran spasial curah hujan tahunan DAS Ciseel; (B) Peta sebaran spasialevapotranspirasi aktual tahunan DAS Ciseel
Figure 8. (A) Map spatial distribution of annual rainfall in Ciseel watershed; (B) Map spatial distribution of annual actualevapotranspiration in Ciseelwatershed
(A) (B)
Gambar 9. (A) Peta geologi pada DAS Ciseel; (B) peta jenis tanah9. ;Figure (A) Geological map of the Ciseel Watershed (B) Map of soil types
(A) (B)
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
kuning dan regosol merupakan tanah peka erosi.Sebaran spasial jenis tanah pada DAS Ciseel dapatdilihat pada Gambar 9 B. Tanah-tanah yang pekaerosi (komplek podsolik dan latosol) hampirmendomisi seluruh wilayah DAS, sedangkan tanah-tanah yang kurang peka terhadap erosi seperti tanahjenis aluvial berada pada hilir DAS.
Peta sebaran kedalaman tanah, permiabilitastanah, kandungan bahan organik tanah dan nilaikepekaan erosi tanah (nilai K) dapat dilihat padaGambar 10 A, B, C dan D.
c. Ketinggian tempat dan kelerengan DAS CiseelPada Gambar 11 A terlihat sebagian besar
wilayah DAS Ciseel berada pada ketinggian 0 - 250
m dpl. Kisaran ketinggian ini hampir menempatilebih 55 % dari luas DAS dan tersebar merata padawilayah tengah dan hilir DAS.
Pada DAS Ciseel terdapat 4 (empat) kelaskelerengan, yaitu kelas 0 - 8 % (luas 37 % dariluas DAS), kelas 8 - 15 % (7 % dari luas DAS), kelas15 - 25 % dengan luas 47 % dari luas DAS dankelas 25 - 40 % mempunyai luas 7 % dari luasDAS (Gambar 12 B). Gambar 11 B menunjukkansebaran spasial kelerengan pada DAS Ciseel . Kelaskelerengan 15 - 25 % yang menempati sebagianbesar kawasan DAS tersebar pada DAS bagiantengah, sedangkan kelas kelerengan yang lainterbesar merata pada hulu dan hilir DAS.
131
(A) (B)
(C) (D)
Gambar 10. Karakteristik masing-masing jenis tanah pada DAS Ciseel, (A) kedalaman horizon, (B)permiabilitas, (C) kandungan bahan organik dan (D) nilai kepekaan tanah terhadap erosi
Figure 10. Characteristic of each type of soil in the Ciseel Watershed, (A) depth of horizon, (B) permeability, (C) organicmatter content and (D) the value of erosion soil sensitivity
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
132
Gambar 11. (A) Peta sebaran spasial ketinggian tempat pada DAS Ciseel; (B) Peta kemiringan lerengFigure 11. Map of elevation ofspatial distribution in the Ciseel watershed; (B)Map of slope
(A) (B)
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi
1. DAS Citanduy HuluSecara Geografis, DAS Citanduy Hulu meliputi 5
(lima) wilayah administrasi kabupaten dan 1 (satu)kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaituKabupaten Majalengka, Kabupaten Garut,Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya,Kabupaten Sumedang dan Kota Tasikmalaya.Kabupaten Tasikmalaya terdapat 13 kecamatanyang masuk wilayah DAS Citanduy Hulu,sedangkan di Kota Tasikmalaya terdapat 6 (enam)kecamatan yang berada diDAS Citanduy Hulu.Untuk Kabupaten Ciamis, DAS Citanduy Hulumeliputi 12 kecamatan, untuk Kabupaten Garutmeliputi 3 (tiga) kecamatan, Kabupaten Majalengkameliputi 2 (dua) kecamatan dan KabupatenSumedang hanya 1 (satu) kecamatan yang beradapada wilayah DAS Citanduy Hulu.
a. Kepadatan geografis DAS Citanduy HuluKepadatan geografis mencerminkan jumlah
penduduk yang mendiami suatu wilayah. Padaperhitungan kepadatan geografis dilakukan faktorkoreksi luasan wilayah administrasi yang masukdalam DAS Citanduy Hulu terhadap luasan wilayahadministrasi yang sebenarnya.
Gambar 12 A menunjukkan sebaran spasialkepadatan geografis pada DAS Citanduy Huludalam kisaran . Semakin tinggi nilaimenunjukkan kepadatan geografis wilayah tersebutmakin tinggi. Kepadatan geografis untuk wilayahDAS Citanduy Hulu berada pada tengah dan hilirDAS.
range range
b. rasio penduduk di DAS Citanduy Hulurasio menunjukkan perbandingan antara
jumlah penduduk pria dan wanita yang bermukimpada suatu wilayah. Semakin tinggi rasio suatuwilayah berarti jumlah penduduk laki-laki lebihbanyak daripada penduduk wanita. Padaperhitungan rasio ini juga dilakukan faktorkoreksi luasan wilayah administrasi yang masukdalam DAS Citanduy Hulu terhadap luasan wilayahadministrasi yang sebenarnya.
Pada peta sebaran rasio dalam bentuk dotmatrik (Gambar 13 B) menunjukkan semakin besardot, semakin besar pula nilai rasio. Pada DASCitanduy Hulu sebaran rasio yang mempunyainilai range besar hampir merata pada seluruhwilayah DAS.
c. Kepadatan agraris DAS Citanduy HuluKepadatan agraris menunjukkan jumlah
penduduk yang bekerja di sektor pertanianpersatuan luas lahan pertanian. Pada perhitungankepadatan agraris juga dilakukan faktor koreksiluasan wilayah administrasi yang masuk dalamDAS Citanduy Hulu dengan luasan wilayahadministrasi sebenarnya.
Berdasarkan peta kepadatan agraris pada DASCitanduy (Gambar 13 C), diketahui bahwa tingkatkepadatan agraris tinggi pada hampir seluruhwilayah DAS. Hal ini menunjukkan bahwa DASCitanduy Hulu terjadi tekanan penduduk yangtinggi terhadap lahan pertanian.
d. Sebaran tenaga kerja DAS Citanduy HuluSalah satu faktor sosial lain yang dinilai pada
penelitian ini adalah sebaran tenaga kerja. Semakin
SexSex
sex
sex
sex
sexsex
JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
133
Gambar 12. DAS Citanduy Hulu (A) Peta sebaran kisaran kepadatan geografis; (B) Peta sebaran rangerasio jenis kelamin; (C) Peta sebaran kepadatan agraris; (D) Peta sebaran tenaga kerja; (E) Petasebaran ketergantungan terhadap lahan; (F) Peta sebaran pendapatan
(A) ; (B); ; (E)
Figure 12. The Citanduy Hulu watershed Distribution range map of Geographic density Distribution rangemap of sex ratios (C) Distribution of Agricultural density; (D) Map of the Labor distribution Map ofReliance on land distribution; (F) Map of income distribution
(A) (B)
(C) (D)
(E) (F)
Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
besar nilainya semakin besar tenaga kerja yang ter-dapat pada suatu wilayah,sehingga sebaran tenagakerja dapat pula menggambarkan penumpukantenaga kerja pada suatu wilayah. Perhitungan tenagakerja juga menggunakan faktor koreksi luas lahan.
Berdasarkan Gambar 13 D diketahui bahwapada DAS Citanduy Huluterjadi penumpukantenaga kerja pada wilayah Kabupaten Ciamis. Halini menunjukkan jumlah tenaga kerja di KabupatenCiamis cukup besar, dengan range 41.796 -63.724.
e. Sebaran ketergantungan terhadap lahanpertanian DAS Citanduy HuluNilai ketergantungan terhadap lahan pertanian
merupakan salah satu kriteria yang dinilai untukfaktor ekonomi. Nilai ini menunjukkan per-bandingan besarnya pendapatan pada sektorpertanian dibandingkan dengan pendapatan total.Semakin tinggi nilainya menunjukkan keter-gantungan terhadap lahan pertanian makin besar.Perhitungan nilai ini juga menggunakan faktorkoreksi perbandingan luas lahan.
Gambar 13 E, menunjukkan peta keter-gantungan terhadap lahan di DAS Citanduy Huludimana sebaran nilai ini berada pada kisaran kurangdari 50 %, artinya berada pada kriteria rendahsampai sedang. Untuk wilayah KabupatenTasikmalaya mempunyai nilai kisaran sedang -tinggi.
f. Sebaran pendapatan regional domestik bruto(PRDB) DAS Citanduy HuluNilai sebaran PRDB digunakan sebagai kriteria
faktor ekonomi yang lain pada penelitian ini. NilaiPRDB mencerminkan tingkat pendapatan suatuwilayah. Perhitungan nilai PRDP pada penelitian inijuga dilakukan koreksi dengan perbandingan luaswilayah administrasi.
Nilai pendapatan suatu wilayah administrasiyang mencerminkan pendapatan pada suatu DAS,pada penelitian ini digambarkan secara kisaran padaGambar 13 F. Terlihat pada grafik pendapatantertinggi berada disekitar wilayah DAS CitanduyHulu bagian Hulu Barat, tepatnya di KabupatenTasikmalaya dan sekitarnya. Secara umum hasilperhitungan tingkat pendapatan perkecamatanberada pada kriteria rendah yakni lebih kecil daripendapatan masing-masing kabupaten.
Secara Geografis, DAS Ciseel berada padawilayah administrasi 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua)
2. DAS Ciseel
kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu KabupatenCiamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar danKota Tasikmalaya.
Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 5 (lima)kecamatan yang masuk wilayah DAS Ciseel, sedang-kan Kota Tasikmalaya terdapat 2 (dua) kecamatanyang masuk wilayah DAS Ciseel. Di KabupatenCiamis, DAS Ciseel meliputi 10 kecamatan, sedang-kan Kota Banjar meliputi 2 (dua) kecamatan.
a. Kepadatan geografis DAS CiseelGambar 13 A menunjukkan tentang sebaran
spasial kepadatan geografis pada DAS Ciseel dalamkisaran range. Semakin tinggi nilai rangemenunjukkan kepadatan geografis wilayah tersebutmakin tinggi. Kepadatan geografis tertinggi untukwilayah DAS Ciseel berada pada wilayah KotaTasikmalaya.
b. rasio penduduk DAS CiseelPeta sebaran rasio dalam bentuk dot matrik
(Gambar 13 B) menunjukkan bahwa semakin besardot, semakin besar pula nilai rasio. Pada DASCiseel sebaran rasio yang mempunyai nilairange besar tersebar pada wilayah DAS yangterdapat pada wilayah Tasikmalya dan Banjar.
c. Kepadatan agraris DAS CiseelBerdasarkan peta kepadatan agraris (Gambar 13
C) DAS Ciseel, diketahui bahwa hampir sebagianbesar wilayah DAS mempunyai tingkat kepadatansedang. Untuk wilayah DAS yang mempunyai tingkatkepadatan tinggi berada disekitar hilir tepatnya diwilayah administrasi Ciamis. Hal ini menunjukkanbahwa DAS Ciseel mempunyai tingkat tekananpenduduk yang rendah terhadap lahan pertanian.
d. Sebaran tenaga kerja DAS CiseelBerdasarkan Gambar 13 D diketahui bahwa
pada DAS Ciseel tenaga kerja tersebar meratadisetiap wilayah DAS. Penumpukan tenaga kerjaterbesar berada disekitar wilayah Kota Tasikmalayadan Kota Banjar.
e. Sebaran ketergantungan terhadap lahanpertanian DAS CiseelGambar 13 E menunjukkan peta ketergantung-
an terahadap lahan di DAS Ciseel. Sebaran nilai iniberada pada kisaran kurang dari 50 %, artinyaberada pada kriteria rendah. Sebaran keter-gantungan terhadap lahan pertanian untuk wilayahKabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayahDAS Ciseel secara keseluruhan mempunyai nilaikisaran tinggi.
Sexsex
sexsex
134JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
Gambar 13. DAS Ciseel(A) Peta sebaran kisaran kepadatan geografis; (B) Peta sebaran range rasio jeniskelamin; (C) Peta sebaran kepadatan agraris; (D) Peta sebaran tenaga kerja; (E) Peta sebaranketergantungan terhadap lahan; (F) Peta sebaran pendapatan
(A) ; (B) ;; (E)
Figure13. The Ciseel watershed Distribution range of Geographic density Distribution range of sex ratios (C)Distribution of Agricultural density; (D) Map of the Labor distribution Map of reliance on landdistribution; (F) Map of income distribution
(A) (B)
(C) (D)
(E) (F)
135Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
f. Sebaran Pendapatan Regional Domestic Bruto(PRDB) DAS CiseelNilai pendapatan suatu wilayah administrasi
yang mencerminkan pendapatan pada suatu DAS,pada penelitian ini digambarkan secara range padaGambar 13 F. Terlihat pada grafik bahwa pen-dapatan tertinggi berada disekitar wilayah DASCiseel bagian hilir, tepatnya di Kabupaten Banjardan Ciamis. Secara umum hasil perhitungan tingkatpendapatan berada pada kriteria rendah yakni lebihkecil dari pendapatan masing-masing kabupaten.
C. Hubungan antara Lanskap Hutan denganKondisi Biofisik dan Sosial Ekonomi
1. DAS Citanduy HuluHasil analisis menggunakan model GWR untuk
mengetahui keeratan hubungan masing-masingfaktor biofisik dan sosial ekonomi dengankeberadaan hutan, dianalisa dengan bantuansoftware spasial statistik SAM versi 4. Nilaikeeratan hubungan didekati dengan nilai korelasidari model GWR masing-masing faktor (biofisikdan sosial ekonomi). Tabel 3 menunjukkan hasil
Tabel 3.Hasil nilai korelasi antara keberadaan hutan dengan faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi padaDAS Citanduy Hulu
Table 3. The results of the correlation presence of forest with biophysical and socio-economicfactors in the Citanduy Huluwatershed
No.Faktor(Factor)
Keberadaan Hutan(Forest existence)
Korelasi(Correlation)
Kuat(Strong)
Sedang(Medium)
Rendah(Low)
Biofisik
1 Curah hujan �
2 Hujan maksimum �
3 evapotranspirasi aktual �
4 Kelerengan �
5 Batuan induk �
6 Kedalam solum tanah �
7 Batuan singkapan �
8 Drainase tanah �
9 Permiabilitas tanah �
10 Erodibilitas tanah �
11 Gradien DAS �
12 Kerapatan Drainase �
13 Rata-rata lereng �
Sosial ekonomi
1 Kepadatan geografis �
2 Kepadatan agraris �
3 Rasio penduduk �
4 Pengelompokan tenaga kerja �
5 Ketergantungan terhadap lahan �
6 Tingkat pendapatan �
Sumber : hasil analisa (Keterangan ( : - Korelasi kuat = r > 0,5
- Korelasi sedang = r = 0,5- Korelasi rendah = r < 0,5- Fungsi pembobot spasial menggunakan Bi-square dan memperhitungkan nilai spasial Kernel
(source) analysis result)explanation)
136JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
analisa nilai korelasi masing-masing faktor biofisikdan sosial ekonomi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapatfaktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi yangmempunyai nilai korelasi kuat terhadap keberadaanhutan pada DAS Citanduy Hulu. Hal inimenunjukkan terdapat hubungan antara keber-adaan hutan pada DAS dengan kondisi faktorbiofisik (lingkungan) dan kondisi sosial ekonomimasyarakatnya. Sedangkan faktor-faktor biofisikdan sosial ekonomi yang mempunyai nilai korelasikuat terhadap keberadaan hutan pada DAS
Citanduy Hulu adalah curah hujan, kelerengan,erodibilitas tanah ( nilai kepekaan tanah terhadaperosi), kerapatan drainase DAS, rata-rata lerengDAS, kepadatan agraris dan ketergantunganterhadap lahan.
Analisis nilai korelasi model GWR meng-gunakan software spasial statistik SAM versi 4ditujukan untuk mengetahui keeretan hubunganmasing-masing faktor biofisik dan sosial ekonomidengan keberadaan hutan, dimana hasilnyadisajikan dalam Tabel 4.
2. DAS Ciseel
No.Faktor(Factors)
Keberadaan Hutan(Forest existence)
Korelasi(Correlation)
Kuat(Strong)
Sedang(Medium)
Rendah(Low)
Biofisik
1 Curah hujan �
2 Hujan maksimum �
3 evapotranspirasi aktual �
4 Kelerengan �
5 Batuan induk �
6 Kedalam solum tanah �
7 Batuan singkapan �
8 Drainase tanah �
9 Permiabilitas tanah �
10 Erodibilitas tanah �
11 Gradien DAS �
12 Kerapatan Drainase �
13 Rata-rata lereng �
Sosial ekonomi
1 Kepadatan geografis �
2 Kepadatan agraris �
3 Rasio penduduk �
4 Pengelompokan tenaga kerja �
5 Ketergantungan terhadap lahan �
6 Tingkat pendapatan �
Tabel 4. Hasil nilai korelasi antara keberadaan hutan dengan faktor-faktor biofisik pada DAS CiseelTable 4. The results of the correlation presence of forest with biophysical factors in the Ciseel watershed
Sumber : hasil analisa (Keterangan ( : - Korelasi kuat = r > 0,5
- Korelasi sedang = r = 0,5- Korelasi rendah = r < 0,5- Fungsi pembobot spasial menggunakan Bi-square dan memperhitungkan nilai spasial Kernel
(source) analysis result)explanation)
137Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )
Hasil analisis menunjukkan terdapat faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi yang mempunyainilai korelasi yang kuat terhadap keberadaan hutan(nilai korelasi kuat) pada DAS Ciseel. Hal inimenunjukkan bahwa tidak hanya faktor biofisik(lingkungan) yang mempengaruhi keberadaanhutan pada suatu DAS, tetapi faktor sosial ekonomimasyarakat yang berada pada DAS tersebut jugabisa mempengaruhi keberadaan hutan, sedangkanfaktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi yangmempunyai korelasi kuat terhadap keberadaanhutan di DAS Ciseel adalah curah hujan,kelerengan, erodibilitas tanah (nilai kepekaan tanahterhadap erosi), kerapatan drainase DAS, rata-ratalereng DAS, kepadatan agraris dan ketergantunganterhadap lahan.
1. Terdapat hubungan yang erat antara keberadaanhutan pada suatu DAS dengan kondisi sosialekonomi masyarakatnya dan kondisi biofisik(lingkungan). Hubungan tersebut dapatdibuktikan dengan menggunakan Metode
2. Aplikasi metode GWR pada DAS berpasanganCitanduy Hulu dan DAS Ciseel menunjukkanbahwa keeratan hubungan antara faktor biofisikdan sosial ekonomi terhadap keberaadaanlanskap ditentukan oleh faktor curah hujan,kelerengan, kepekaan tanah terhadap erosi,kerapatan drainase DAS, rata-rata lereng DAS,kepadatan agraris dan ketegantungan terhadaplahan.
3. Rendahnya korelasi yang ditunjukkan melaluirasio penduduk, tenaga kerja dan tingkatpendapatan diduga merupakan konsekuensi darikeberadaan Kota Tasikmalaya dan Banjarsebagai outlet penyedia kesempatan kerja danpendapatan bagi masyarakat di wilayah DASCitandui Hulu dan DAS Ciseel.
Penentuan arahan spasial keberadaan hutan yangditentukan oleh faktor biofisik (curah hujan,kelerengan dan jenis tanah) perlu ditinjau kembalidengan memasukkan faktor sosial ekonomi
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
Geographically Weighted Regression models (GWR).
masyarakat dan faktor keberadaan DAS.Pertimbangan tersebut diperlukan agar rencanapembangunan kehutanan dalam melestarikansumberdaya hutan dan air dilakukan sesuai dengankenyataan lapangan,sehingga mendukungpengentasan kemiskinan serta meminimalkankonflik dengan masyarakat.
Arsyad, S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. IPBPress. Bogor.
Becerra, E.H., 1995. Monitoring and Evaluation ofwatershed Management Project Achivements.FAOConservationGuide24.FAOUN.Rome.
Diaz, N. and Apostol, D. ____ .ForestLandscapeAnalysis and Design.A Processfor Developing andImplementing LandManagementObjectives for LandscapePatterns.USDA Forest Service.PacificNorthwest Region.United State.
Fotheringham, A.S.,Charlton, M., and Brunsdon,C. 2002 .Geog raphica l l y WeightedRegression. ESRC National Centre forResearch Methods.NCRM Methods ReviewPapers. [terhubung berkala].
Html [11 Desember 2010]
Green, B.H., E.A. Simmons, and I. Woltjer. 1996.Landscape Conservation: Some StepsTowards Developing a New ConservationDimension. A draft report of the IUCN-CESPLandscape Conservation Working Group. Dept.Agriculture, Horticulture and Environment,WyeCollege, Ashford, Kent, UK
Jennings, S., Jarvie, J. 2002. A Sourcebook forLandscape Analysis of High ConservationValue Forests.
Keputusan Presiden Republik Indonesia, 1990.Kepres No. 92 tentang Pengelolaan KawasanLindung. [terhubung berkala].
[11november 2011].
Maryani, R. 2010. Manajemen Lanskap HutanBerbasis Daerah aliran Sungai (DAS).Rencana Penelitian Integratif 2010 - 2014.Pusat Penelitian Sosial Ekonomi danKebijakan Kehutanan. Badan Penelitian dan
DAFTAR PUSTAKA
http://ncg.nuim.ie/GWR.
http://www.dephut.go.id/bksda.
138JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Hal. 122 - 139
Pengembangan Kehutanan. KementerianKehutanan. Bogor.
Paimin, Sukrisno dan Purwanto. 2006. Sidik CepatDegradasi Sub Daerah Aliran Sungai. PuslitHutan dan Konservasi Alam. BadanPenelitian dan Pengembangan. DepartemenKehutanan. Bogor.
Pawitan, H. 2004. Aplikasi Model erosi dalamPerpektif Pengelolaan Derah Aliran Sungai. IProsiding Seminar Degradasi Lahan danHutan. Masyarakat Konservasi Tanah danAir Indonesia. Universitas Gadjah Mada danDepartemen Kehutanan.
Surat Keputusan Menteri Pertanian, 1980, Nomer837/kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.[terhubung berkala].
..... [11 November 2011]
Thiago F. Rangel, Jose,A. F. Diniz-Filho and Luis,M. B. 2010. SAM: a comprehensiveapplication for Spatial Analysis inMacroecology.
.
http://www.deptan.go.id/
Journal compilation of
Ecography
139Pengaruh Dinamika Spasial Sosial Ekonomi Pada Suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap ..... Edy Junaidi, Retno Maryani( )