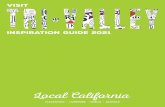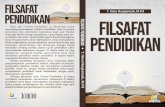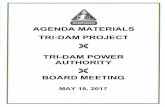Penulis M. Chairul Basrun Umanailo, S.sos Tri Yatno, S ... - OSF
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Penulis M. Chairul Basrun Umanailo, S.sos Tri Yatno, S ... - OSF
“CATATAN DI AKHIR PERKULIAHAN”
KAJIAN DAN ANALISIS SOSIOLOGI
DALAM BENTUK KUMPULAN ESSAY,
MAKALAH DAN OPINI
Penulis M. Chairul Basrun Umanailo, S.sos
Tri Yatno, S.Pd.B
Editor
ARIHAN, S.Pd
CATATAN DI AKHIR PERKULIAHAN
(Kajian dan Analisis Sosiologi
Dalam Bentuk Kumpulan Essay, Makalah dan Opini)
iv + 107 hal; 14 x 20 cm
Didukung Oleh:
Fakultas Hukum Prodi Dharmaduta
Universitas Iqra Buru STABN Raden Wijaya
Hak Cipta @ M. Chairul Basrun Umanailo. Tri Yatno. 2015
Cetakan 1, 2015
Cetakan 2, (Revisi) 2015
Infinite Publisher
ISBN : 978-602-1087-84-4
ii
PENGANTAR PENULIS Belajar adalah “Anugrah”, ketika kesempatan itu
datang sekiranya Tuhan menginginkan manusia untuk
berubah menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.
Begitu juga apa yang saya dapatkan selama menjalani
studi di Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, banyak
pengalaman yang tidak saya ingin tinggalkan begitu
saja dengan kesungguhan hati maka keinginan menulis
buku ini semakin kuat.
Buku ini berupaya menyajikan kajian-kajian yang
sederhana tentang perubahan masyarakat, postmodern,
politik, maupun kajian-kajian sosial dari berbagai
realitas yang terjadi dalam masyarakat, dengan kalimat
yang sederhana bahkan tidak teratur dalam strukturnya,
namun demikian penulis tetap berupaya untuk
mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki, serta
penulis yakin bahwa sesuatu yang “besar” selalu
berawal dari kesalahan-kesalahan yang secara terus
menerus membuka pikiran seseorang untuk
menemukan sesuatu yang lebih baik lagi.
Buku ini bukanlah sebuah karya teoritis yang
fenomenal, malah hanya kumpulan tugas-tugas yang
penulis kumpulkan kembali selama perkuliahan
berlangsung, bagi penulis tugas tersebut memiliki arti
penting untuk bisa dikembangkan pada tataran yang
lebih baik lagi.
Tulisan yang penulis rangkum dalam buku ini, ada
sebagian kecil merupakan kerja kelompok yang
merupakan kontribusi penting dalam menyelesaikan
tugas perkuliahan yang sementara berlangsung, maka
dari itu penulis juga berkewajiban mengucapkan terima
iii
kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman
sekelas yang pernah menjalani perkuliahan bersama-
sama dengan penulis.
Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada mereka yang telah memberikan dorongan
moral, khusunya, Istri tercinta, Yusmidar Umanailo serta
kedua anak-anakku, Annisa Retrofilia Umanailo dan
Askar Daffa Sophia Umanailo, yang selalu mendorong
dan memberikan kekuatan moral selama penulis
mengikuti program S2. Juga kepada seluruh Dosen-
dosen di Prodi Sosiologi Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, Dr. Argyo Demartoto M.Si.
yang mau memahami kondisi penulis dan terus
membantu selama penulisan buku ini dilakukan. Salam
hormat kepada Dr Mahendra Wijaya, MS, Dr. Drajat Tri
Kartono, M.Si, Prof. Soemanto MA, Drs. Y. Slamet,
M.Sc.,Ph.D, Dr. Ahmad Zuber, D.E.A., yang selalu
menjadi inspirator selama perkulihaan berlangsung.
Kepada Kakanda Rusnawati Umanailo, penulis
sangat berterima kasih atas dukungan serta perhatian,
Mas Arihan untuk Edit-nya, dan Tidak lupa, teman-
teman Mahasiwa Pascasarjana Sosiologi di UNS, juga
teman-teman khususnya di angkatan 2013 S2 Program
Sosiologi UNS, yang tidak dapat saya sebutkan
seluruhnya, yang ikut berdiskusi untuk membantu
penyusunan buku ini.
Melalui tulisan-tulisan dalam buku ini, sekiranya
ada nilai lebih yang bisa kita dapatkan bersama-sama,
dan semoga juga buku ini bermanfaat bagi kita semua.
Awal 2015
Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Judul.............................................................................................. i
Pengantar Penulis.................................................................... ii
Daftar isi....................................................................................... iv
Agama Dalam Identitas................................................... 1
Budaya Gosip Mengkonstruksi Opini Publik................. 5
Daur Ulang Konsumerisme Menuju Konstruksi
Masyarakat Modern........................................................ 7
Pierre Bourdieu; Menyikap Kuasa Simbolik................. 20
Perang Itu Belum Usai.................................................... 24
Tragedi Kabinet Kerja Jokowi........................................ 27
Memahami Kontur Konflik Pada Cyber Community.... 30
Konsumerisme................................................................ 39
Money Politic Menjadi Agama Baru.............................. 50
Pidato Dan Penghancuran Label Calon Presiden 2014.. 54
Postmodernisme Dalam Pandangan Jean Francois
Lyotard............................................................................ 58
Modernisasi Pedesaan..................................................... 73
Dualisme Eksistensi Kondom….................................... 81
Dominasi Modal Ekonomi Atas Ranah Politik.............. 93
Kebijakaan Politik Pendidikan Yang Merakyat…..........99
DAFTAR PUSTAKA
Biografi Penulis
1
AGAMA DALAM IDENTITAS M. Chairul Basrun Umanailo
Bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan kolom,
kolom dalam baris Kartu Tanda Penduduk yang
mengisyaratkan agama bagi setiap pemiliknya. perdebatan
terus berlanjut dan tidak bisa dihentikan atas nama
perdamaian. Sebab musabab dari perdebatan yang panjang
adalah ketika Menteri Dalam Negeri (Cahyo Kumolo)
2
melemparkan wacana penghapusan kolom agama dalam KTP
sebagai keberpihakan pada kaum minoritas di Indoensia.
Dalam tulisan ini pun saya tidak membela pada siapa
yang benar, semurni logika saya berpikir bahwa agama
merupakan identitas kultural dan sangat sensitif ketika
pemaknaan terhadap agama itu sendiri harus bertentangan.
Pada waktu negara ini dibangun, sadar atau tidak agama lah
yang kemudian menjadi katalisator, identitas para pendahulu
kita bahkan Founding Father selalu terdepan dalam
berkecampuk dengan berbagai situasi penguasaan
kalonialisasi. Sebut Saja Agus Salim, dengan percaya dirinya
hingga ke Negeri Belanda tetap menggunakan sarung sebagai
identitas Islamnya yang kuat dan itupun tidak menjadi
masalah dalam berdiplomasi atau bernegara pada saat itu.
Dalam beberapa kutipan yang coba saya rangkum,
seraya ingin memahami apa itu konsep agama? kembali kita
mempertanyakan agama pada titik awal dimana kesadaran
anda maupun saya masih berada pada tataran “mencari”.
Seorang filosof berkembangsaan Pakistan, Sir DR
Mohammad Iqbal, menulis bahwa sebenarnya “agama” itu
merupakan suatu pernyataan utuh dari manusia (Damani
2002). Menurut hendro puspito agama adalah suatu jenis
sistem sosial yang di buat oleh penganut-penganut nya yang
berproses pada kekuatan-kekuatan non empiris yang di
percayainya dan di daya gunakan nya untuk mencapai
keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umum nya
(B.R Wilson). Lain lagi ketika Emile Durkheim seorang
Sosiolog yang menyatakan bahwa agama merupakan
proyeksi pengalaman sosial.
Agama merupakan bentuk kesadaran manusia yang
termanifestasi pada suatu kultur dimana manusia awalnya
terpasung karena keturunan dan membuat kemungkinan
untuk berubah seiring pembentukan kesadarannya.
Kesadaran terbentuk oleh dan dari dirinya sendiri. Menurut
Berger, manusia secara ontogenetis dilahirkan dalam bentuk
kedirian yang “belum selesai”. Keberadaannya di-dunia,
3
dengan demikian, merupakan proses untuk “menjadi
manusia”. Manusia, dalam konteks tersebut, secara terus-
menerus melakukan proses eksternalisasi diri. Ia selama
proses tersebut mencurahkan makna-makna ke dalam realitas
(Irfan Noor). Maka Agama menjadi sebuah cerminan bagi
setiap individu dalam keseharian yang berhadapan dengan
realitas sosial. Apa yang saya anggap sebagai “terpasung”
merupakan bagian keberhinggaan yang sering di temukan
dalam kajiannya Peter L Berger.
Maka ketika seseorang tidak mampu mengurai
keterpasungannya dalam realitas sosial sulit baginya untuk
hidup selayaknya individu yang mampu melepaskan
keterpasungannya itu. Hal ini terkait dengan identitas yang
ketika dalam pertukaran simbolik menjadi modal utama
dalam berinteraksi. Kultur budaya kita memiliki unsur
pemaksa, anda akan sulit bereksistensi ketika harus
berhadapan dengan kelompok yang secara Sosiologis
memiliki homogenitas. Dan hasil dari situasi seperti ini
adalah anomaly. Agama merupakan instrument penyusun
keteraturan sosial, agama mempolarisasi masyarakat pada
tiap-tiap diferensiasi dengan berbagai aturan serta norma
yang ditetapkan.
Agama dalam identitas merupakan penanda bahwa
eksistensi agama sebagai katalisator kehidupan manusia itu
jelas sangat berarti. Seluruh agama memiliki aturan jelas
serta orientasi dan perilaku dalam menjalankan agama pun
sudah ditetapkan. Artinya agama mempolarisasikan individu
sesuai tujuan agama itu sendiri. Dan ketika seseorang
memilih untuk memeluk salah satu agama tentunya memiliki
argumentasi yang kuat, seperti misalnya rasa nyaman, jati
diri serta perlindungan.
Kembali saya singgung kolom KTP tentang agama,
sebab bukan sekedar tulisan Islam, Kristen, Hindu, Budha
serta Konghucu, melainkan tersirat identitas kita yang sangat
kuat sebagai individu yang memiliki proyeksi kehidupan, apa
jadinya ketika seseorang tidak memiliki proyeksi tentang
4
kehiduapnnya sendiri. Lagi-lagi keteraturan sosial kita akan
terusik. Saya bisa bayangkan ketika KTP tanpa kolom agama
maka kebebasan itu akan menjadi liar saat seseorang akan
keluar masuk tempat ibadah, tanpa pernah merasa dia bagian
dari ibadah tersebut, dan akan seenaknya mengaburkan
agama-agama yang ada dengan ajaran intepretasinya.
Seingat saya, Max Weber mampu mengurai
kapitalisme dari bagian yang menceritakan etos kerja
berdasarkan agama, Jadi ketika usulan Pemerintah untuk
menghapus kolom agama dalam KTP berarti pemerintah
sendiri yang menghancurkan identitas rakyatnya,
menghancurkan diferensiasi dan meleburkan tata nilai yang
berhasil mengakomodir kehidupan sosial kita. Rakyat masih
butuh identitas, Rakyat masih butuh keteraturan, ingat
Bangsa Indonesia bisa hancur hanya karena 3 hal; 1, Agama
di pasung, 2. Ekonomi di kebiri, 3. pemimpin ber“Onani”.
Semoga kesadaran itu bisa tumbuh.
5
BUDAYA GOSIP
MENGKONSTRUKSI
OPINI PUBLIK
M. Chairul Basrun Umanailo
Masyarakat Indoensia tidak lagi terpolarisasi pada
segmentasi ekonomi antara bourjouis dan proletar yang terus
tarik menarik pada siklus yang tanpa berkesudahan ujungnya,
begitupun ruang-ruang publik sejatinya menjadi ekspresi
bersama, terkekang dengan lingkaran kapitalis yang semakin
mendominasi bahwasanya ruang publik hanyalah imajinasi
bukan lagi fakta atas kenyataan bahwa manusia berpijak atas
kesadarannya sendiri untuk mempertahankan hidup dan
eksistensinya.
Opini publik semakin mengkerucut pada nadir
intelektual yang ditopang oleh sumulasi media, apa yang kita
pahami tentang opini publik bukanlah seperti yang
disampaikan “Sutinah”, bahwasanya opini publik adalah
kumpulan opininya banyak orang ataupun pendapat semua
orang. Sutinah sangat yakin karena kata opini maupun publik
bukan milik orang pintar, pejabat atau pekerja di media
namun suatu kata yang bisa mewakili tukang bakso, kuli
bangunan bahkan pelacur sekalipun, untuk mengutarakan
bahwa apa yang dia konstruksikan dalam memahami
permasalahan yang dihadapi.
6
Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana
seharusnya media memposisikan opini publik sebagai sebuah
ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama
diantara para anggota sebuah kelompok atau publik,
mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum.
Bukan sebaliknya media mengkonstruksikan wacana untuk
dijadikan opini publik. Contoh yang bisa kita dapatkan ketika
Pilpres 2014, dimana hampir semua media mengibarkan
bendera “perang”, berlomba-lomba menciptakan narasi untuk
mengkonstruksi opini publik kepada salah satu calon.
Alhasil, dan itu sangat berhasil, dengan terpolarisasinya
masyarakat dalam segmentasi kelompoknya masing-masing.
Fakta yang masih berwujud gosip dipaksa untuk
membenarkan narasi dan melahirkan opini yang
menyesatkan. Pada akhirnya media dianggap sebagai
konduktor konflik yang mumpuni.
Pengaruh gosip sebagai hiburan dalam masyarakat
membuka ruang tersendiri hingga menyebabkan
terbangunnya wacana dan menjadi opini publik adalah suatu
dinamika sosial yang memiliki Multi-efek bagi kehidupan
sosial masyarakat. Gosip yang sudah terkena pengaruh
industrialisasi dalam kerangka Infotainment menjadikan
pembedaan antara mana fakta dan mana spekulasi semakin
menipis menyebabkan masyarakat semakin terjebak pada
konstelasi pemikiran yang menyeret egosentri pada
keberpihakan kultural.
Seseorang dengan mudahnya mengkonstruksi opini
publik terhadapnya (seijin media) dengan menciptakan
sensasional seperti yang tercipta dalam simulacra, pencitraan
sebagaimana yang dikehendaki menjadikan opini publik
semakin “diperkosa” oleh sentilan-sentilan nakal gosip dari
mereka yang memiliki kemampuan. Maka ketika gosip
dijadikan bahan bakar untuk membangun opini publik maka
jangan khawatir bahwasanya opini publik akan berganti
nama menjadi “opini gossip”.
7
“DAUR ULANG” KONSUMERISME
MENUJU KONSTRUKSI MASYARAKAT MODERN
M. Chairul Basrun Umanailo
Puji dan syukur saya panjatkan pada Sang khalik, ketika dipertemukan dengan tulisan-tulisan kritis tentang konsumerisme membuat tumbuh kesadaran saya untuk mendaur ulang pemaknaan tentang konsumerisme sebagai sebuah “gejala manipulasi tingkah laku manusia”. Sebelum jauh kita bergulat dengan konsumerisme itu sendiri, saya coba mengajak anda untuk sekedar merefresh pemikiran kita untuk menkonstruksi kembali apa yang dikehendaki oleh pemikir-pemikir terdahulu tentang konsumerisme.
Tidak lepas dalam ingatan kita, bagaimana Jean Baudrilard menelanjangi konsumerisme dengan karya besar tentang masyarakat konsumsi, Yasraf Amir Piliang mencoba untuk meretas konsumerisme lewat tafsir Cultural Studies atas matinya Makna, sementara itu Ritzer, Douglas, maupun Barry Smart yang masih setengah hati menafsirkan makna dari konsumerisme. Kesemuanya itu adalah upaya mengkonstruksi dan meleburkan nilai-nilai yang terkandung dan terbangun
8
dalam suatu essay lepas untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsumerisme siap menerkam kita kapan saja dan dimana saja.
Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif. Masyarakat yang terus menerus berkonsumsi. Namun konsumsi yang dilakukan bukan lagi hanya sekedar kegiatan yang berasal dari produksi. Konsumsi tidak lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan fungsional manusia. Konsumsi telah menjadi budaya, budaya konsumsi. Sistem masyarakat pun telah berubah, dan yang ada kini adalah masyarakat konsumen, yang mana kebijakan dan aturan-aturan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan pasar (Budaya Konsumen).
Awal terbangunnya konsumerisme ketika orang mulai mengagumi keberadaan teori konsumsi, terjadi pergeseran makna pada tataran teoritis, individu menyadari bahwa hidup bukan sekedar menjangkau atau mencari sumber ekonomi namun juga bagaimana mengelola sumber-sumber itu agar bertahan lama bahkan mungkin selamanya untuk kesehjateraan individu. Perubahan cara produksi diikuti dengan kekacauan social skala besar yang akhirnya menyebabkan tumbangnya cara hidup tradisional yang berbasis pada produksi pertanian (Ritzer. 2011).
Ada tendensi evolusi dalam perjalanan konsumerisme sebagai penjelmaan nilai lebih dari suatu komoditas akibat bergesernya fungsi barang, bagi saya keberadaan konsumerisme bukan tergantung pada waktu, melainkan kesempatan dalam kepemilikan capital dan tersedianya sumber-sumber ekonomi yang mengarah pada terjadinya hukum dominasi bukan hukum permintaan. Terjadi migrasi besar-besaran ke pusat-pusat kota yang baru terbentuk. Kelas-kelas
9
social yang dulunya muncul sebagai budak kini ditransformasikan menjadi buruh yang diupah. Kita bisa mengikuti urutan sejarah system industrial silsilah/asal usul konsumsi: (1) tatanan produksi menghasilkan mesin/kekuatan produkstif, (2) ia menghasilkan modal/kekuatan produktif yang masuk akal, (3) ia menghasilkan tenaga kerja bergaji, kekuatan produktif yang abstrak, tersistimatisir, yang secara mendasar berbeda dengan pekerjaan nyata dan pekerjaan tradisional, (4) terakhir ia melahirkan kebutuhan-kebutuhan, system kebutuhan, permintaan/kekuatan produktif sebagai kumpulan yang dirasionalkan, disatukan, dan diawasi. Semua itu dibuat sebagai unsur system, dan bukan hubungan sebagai individu dengan objek, menunjukan bahwa hubungan manusia dengan objek-objek hubungan manusia dengan dirinya sendiri dipalsukan, dikelabui, dimanipulasi (M. Chairul Basrun Umanailo).
Hampir semua filsuf social yang menulis tentang kebangkitan konsumsi sebagai gejala individual yang mengancam tatanan social. Weber (1904) memandang konsumsi sebagai ancaman bagi etika Protestan kapitalis. Durkheim (1964) menyamakan konsumsi dengan anomi pengancam masyarakat yang bisa diperbaiki dengan interelasi-interrelasi fungsional dalam pembagian-pembagian kerja yang ditemukan dalam produksi (Ritzer. 2011). Bagi Ekonom, inilah “Utilitas” keinginan memperoleh satu kebaikan tertentu yang khusus di akhir konsumsi. Maka kebutuhan telah terpenuhi oleh barang-barang yang tersedia, hobi yang diarahkan oleh potongan produk yang tersedia di pasar: inilah hakikat permintaan yang sanggup dipenuhi (Baudrillard. 2013).
10
Konsumsi adalah system yang menjalankan urutan tanda-tanda dan penyatuan kelompok. Jadi konsumsi itu sekaligus sebuah moral (sebuah system nilai ideology) dan system berkomunikasi, struktur pertukaran. Menurut hipotesa ini, dan juga paradoks mengenai hal itu munculnya konsumsi didefenisikan sebagai kenikmatan yang eksklusif. Sebagai logika sistem, sistem konsumsi didirikan di atas dasar pengingkaran kenikmatan. Disana kenikmatan tidak lagi muncul sama sekali sebagai tujuan rasional, tetapi sebagai rasionalisasi individu pada suatu proses yang bertujuan lain. Kenikmatan akan memberi batasan konsumsi bagi dirinya, otonom, dan akhir konsumsi (Ritzer. 2011).
Konsumsi, menurut Yasraf, dapat dimaknai sebagai sebuah proses objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-objek sebagai medianya. Maksudnya, bagaimana kita memahami dan mengkonseptualisasikan diri maupun realitas di sekitar kita melalui objek-objek material. Disini terjadi proses menciptakan nilai-nilai melalui objek-objek dan kemudian memberikan pengakuan serta penginternalisasian nilai-nilai tersebut
Marx membahas konsumsi secara langsung dan rinci dalam Grundrisse. Sebahagian besar pembahasan itu tentang membangun hubungan dialektis tiga rangkap antara konsumsi dan produksi. Pertama, konsumsi selalu merupakan produksi, dan produksi selalu merupakan konsumsi artinya dalam memproduksi objek selalu ada konsumsi tenaga bahan dan tenaga manusia; sedangkan dalam mengonsumsi objek, ada aspek tertentu dari konsumen yang diproduksi. Kedua, produksi dan konsumsi bersifat interdependen. Produksi menciptakan objek yang
11
diperlukan untuk konsumsi dan konsumsi menciptakan motivasi untuk produksi. Ketiga, produksi dan konsumsi saling menciptakan. Produksi selesai melalui konsumsi yang menciptakan kebutuhan akan produksi lebih lanjut.
Sebaliknya konsumsi hanya tercipta sebagai salah satu realitas materi melalui produksi karena kebutuhan yang mendorong konsumsi hanya menjadi konkret dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu yang telah di produksi (Baudrillard. 2013). Menurut Gervasi: “pilihan-pilihan tidak dibuat secara kebetulan, tetapi terkontrol secara social, dan mengambarkan model budaya di tengah budaya yang mereka buat. Orang tidak menghasilkan juga tidak mengkonsumsi benda apa saja: mereka harus memiliki beberapa arti menurut pandangan sistem nilai. Tujuan ekonomi bukanlah memaksimalkan produksi untuk individu, tapi maksimalisasi produksi yang berhubungan dengan sistem nilai masyarakat (Parsons) (Piliang. 2004).
Kerangka pikir yang membedakan antara nilai guna yang sesunguhnya (true use values) dengan ciri-ciri palsu objek yang difetisisasikan dan dialienasikan. Kerangka pikir dan pembedaan ini mendefenisikan pendekatan Marx bahwa konsumsi atas sesuatu yang secara fungsional dianggap berguna akan dilegitimasikan sebagai kebutuhan, sedangkan semua konsumsi lain yang terkait dengan kemewahan dianggap sebagai kemerosotan moral (Ritzer. 2011). Penghasilan, belanja prestise, membentuk lingkaran setan dan kebingungan, lingkaran kejam konsumsi, yang didasarkan atas kegairahan kebutuhan yang disebut”Psikologis”, yang berbeda-beda kebutuhan fisiologis dalam apa yang mereka dasarkan pada “penghasilan yang tergantung pada orang yang
12
berkuasa” dan kebebasan memilih, akhirnya menjadi Manipulable merci. Untuk menerima bahwa kebebasan dan kedaulatan konsumen hanyalah perbuatan mistifikasi (memperdaya orang banyak) (Baudrillard. 2013).
Horkheimer dan Adorno menggambarkan industri kebudayaan disorganisasi dengan berpusat pada model-model produksi massa Fordis. Fordisme tidak hanya menghasilkan barang konsumen yang homogeny, tapi juga standarisasi dan komodifikasi produk-produk kebudayaan buatan pabrik. Marcuse menyatakan „orang mengenali dirinya dari komoditas-kontrol sosial ditentukan dari kebutuhan-kebutuhan baru yang ditimbulkannya. Marcuse mendiagnosa persoalan pada masyarakat konsumen adalah kenikmatan yang tidak cukup. Kebudayaan konsumen dalam kapitalisme kontemporer bukanlah tempat bagi hedonism yang tak terkendali, melainkan tempat bagi kesenangan-kesenangan yang terkendali secara birokratis dan dirasionalisasi (Ritzer. 2011).
Garis batas “palsu”, kesenangan pada TV atau kesenangan memiliki Villa adalah nyata sebagai “kebebasan yang sebenarnya”, tak seorangpun menghidupkan sebagai alienasi (Baudrillard. 2013). Tujuan konsumsi merupakan paksaan dan dilembagakan bukan sebagai hak atau sebagai kesenangan, tetapi sebagai tugas (devoir) dari warga Negara (Ritzer. 2011).
Analisis Simmel tentang peranan uang dalam modernitas. Inti dari argument Simmel ialah bahwa pertumbuhan dan reifikasi kebudayaan objektif juga bermanfaat karena menyediakan lebih banyak peluang bagi individu untuk mengekspresikan kebebasan dan individualitas. Bukannya menggunakan macam-macam
13
komoditas yang sangat banyak ini, malah seringkali kitalah yang dimanfaatkan oleh komoditas-komoditas itu (Baudrillard. 2013).
Veblen mengutarakan; kelas atas menggunakan konsumsi berlebihan untuk membedakan diri dari kelas-kelas di bawahnya dalam Hierakhi sosial, sementara kelas-kelas bawah berupaya (dan biasanya gagal) meniru pola konsumsi tingkatan diatas mereka. Dorongan untuk meniru ini memicu efek „mengalir ke bawah‟, yaitu kelas atas menjadi penentu bagi semua konsumsi yang terjadi dibawahnya. Praktik-praktik konsumsi yang dilakukan leisure class, kelas yang lebih banyak memiliki waktu luang ketimbang bekerja dicela-cela waktunya karena dia menggunakan kecakapan kerja dan produksi. Jadi dengan mengkonsumsi objek, sesungguhnya kita sedang mengonsumsi bermacam-macam makna yang terkait dengan kelas (Baudrillard. 2013).
De Certeau (Ritzer. 2011), menjelaskan; gagasan utamnya ialah bahwa konsumen bukan hanya dikontrol oleh manipulasi pemasaran seperti yang ingin diyakinkan kaum Marxis, Neo-Marxis, dan lain-lain, tetapi konsumen sendiri juga menjadi manipulator aktif. Bukannya patuh menggunakan jasa dan barang konsumen sesuai yang diharapkan, konsumen menggunakan jasa dan barang itu dengan cara sendiri sesuai kebutuhan dan kepentingannya.
14
OBJEK KONSUMSI
Adam Smith (Ritzer, 2011), mendekati studi objek-objek konsumsi dengan konsep komoditas. Smith dan Marx, komoditas terutama dipandang sebagai bagaian dari proses produksi. Jean Baudrillard menulis dalam the system of objects bahwa untuk menjadi objek konsumsi, terlebih dahulu sebuah objek harus menjadi tanda. Jadi memahami konsumsi kita perlu mampu membaca barang konsumen sebagai serangkaian tanda-sama dengan bahasa yang memerlukan penafsiran.
Baudrillard menerangkan bahwa sebuah objek mulai menjadi objek konsumsi bila tidak lagi ditentukn oleh hal-hal berikut: (1) tempat objek di dalam siklus produksi; (2) kegunaan fungsional objek; atau (3) makna simbolis objek. Objek konsumen adalah pesan, barang konsumen adalah peranti lunak dan peranti keras dalam sebuah sistem informasi yang urusan utamanya ialah memantau kinerjanya sendiri. Metafora konsumsi sebagai manipulasi tanda lebih berguna untuk membedakan antara konsumsi dan bahasa dari pada untuk menyamakannya. Barang konsumen bekerja serasi menciptakan satu keseluruhan bermakna dan konsisten. Membeli sepasang sepatu baru menciptakan ketidak serasian dengan setelan yang lama. jadi, orang harus membeli rok baru, blus baru, dan dompet baru agar semua objek konsumen bisa dipadu padankan.
15
SUBJEK KONSUMSI Gabriel dan Lang menunjukan tipe konsumen
sangat bermacam-macam: korban, pemilih, komunikator, pencoba-coba, pencari identitas, hedonis, artis, pemberontak, aktivis, atau warga. Daftar ini memang tidak lengkap, tetapi berhasil menyampaikan fakta bahwa ada keanekaragaman di kalangan konsumen. Habitus adalah sistem dan struktur-struktur, penstrukturan yang bergabung menjadi keseluruhan teratur, yang diciptakan guna menanggapi kondisi-kondisi objektif dan dipelajari melalui sosialisasi. Ciri terpenting habitus ialah habitus bukan mengontrol actor, tetapi dapat dikalahkan melalui refleksivitas. Dalam Distinction, Bourdieu menghubungkan habitus dengan selera. Dengan konsep habitus, Bourdieu sanggup menghubungkan mikropraktik-mikropraktik tampak voluntaristis yang biasa diasosiasikan dengan selera mikro struktur kelas-kelas kapitalis. Dalam pandangan ini, konsumsi bisa dianggap sebagai pilihan-pilihan gaya hidup strategis sadar yang dibuat konsumen dengan dilatarbelakangi selera-selera tak sadar yang menjadi ciri suatu habitus kelas (Ritzer. 2011).
Konsumsi dibayangkan sebagai sebuah ranah tempat niat dan tujuan aktor-aktor individu ditopang dan ditransformasi melalui manipulasi-manipulasi eksperimental pada sistem objek-objek. Bauman berargumen bahwa pengalaman kebebasan yang dikaitkan dengan konsumsi akan menghindari dua masalah ini. Pertama, karena wilayah konsumsi modern lebih berpusat pada gaya hidup dari pada barang. Kedua, mereka yang melakukan belanja gaya hidup dapat bereksperimen dengan bentuk-bentuk komunitas yang bisa dimasuki dan ditinggalkan tanpa harus mengompromi kebebasan individu mereka (Ritzer. 2011).
16
TEMPAT-TEMPAT KONSUMSI
Pendekatan Benjamin pada konsumsi berpusat pada peranan yang dimainkan perubahan teknologi. Munculnya foto dan ancaman yang dibawanya terhadap lukisan. Studi sejarah teori sosial dan konsumsi Rosalind Williams dapat dianggap menghubungkan karya Benjamin dengan konsep anomi Durkheim. Williams menekankan peranan yang dimainkan tempat-tempat khusus ini (pekan raya dunia, toko serba ada) dalam membangkitkan dan membakar hasrat konsumen, juga dalam menumbuhkan masyarakat konsumen. Eksposisi dunia dan toko-toko serba ada, dalam periode ini merupakan dunia-dunia impian yang dipilih untuk membangkitkan minat konsumen terhadap konsumsi, menghibur konsumen, menyediakan tempat, barang, dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan imajinasi mereka. Tempat-tempat ini memikat dan menggoda konsumen dengan fantasi. Upaya lebih kontemporer ditawarkan Ritzer untuk menyemimbangkan minat-minat tradisional pada konsumen, objek-objek konsumen, dan proses konsumsi, dengan lebih banyak mencurahkan perhatian pada tempat-tempat konsumsi. John Urry mnyebut tempat-tempat ini tempat konsumsi atau “tempat untuk konsumsi”… Konteks yang di dalamnya barang dan jasa diperbandingkan, dievaluasi, didibeli dan dipergunakan. Di satu sisi, tempat-tempat ini dipaksa untuk melakukan rasionalisasi dan birokratisasi, khususnya jika tempat-tempat itu berusaha melayani klien dan pelanggan dalam jumlah besar serta beroperasi di sejumlah lingkungan geografis yang berbeda.
Meskipun disebut-sebut sebagai dunia impian sebagian darinya paling tidak, tempat-tempat konsumsi
17
yang dibahas sejauh ini sangat material, misalnya; restoran cepat saji, toko serba ada, kapal pesiar dan sebagainya. Namun salah satu kecendrungan terpenting ialah kearah munculnya sarana konsumsi yang „didematerialisasikan‟. Membahas Dematerialisasi ini terutama dalam hubungannya dengan barang konsumen dan fakta bahwa semakin banyak barang konsumen yang bersifat non-material (maksudnya berbentuk jasa), gagasan bahwa barang materialpun mempunyai lebih banyak unsur non-materialnya (misalnya, citra iklan, unsur desain, dan unsur pengemasan) (Ritzer. 2011).
PROSES KONSUMSI Studi menarik mengenai proses konsumsi ialah A
Theory of Shopping karya Daniel Miller (Ritzer. 2011)., tiga tahap menuju konsumsi. Tahap pertama adalah visi pengalaman berbelanja murni, biasa disebut „real shopping‟. Dalam visi ini, konsumen hedonistis secara tak bertanggung jawab menjarahi dan meludeskan sumber daya, berkolaborasi dengan kapitalisme dalam merusak diri sendiri dan bumi. Tahap kedua, konsumen menerapkan strategi dan ketrampilan menghemat. Dalam praktik, biasanya shopping dijelaskan sebagai kesempatan untuk menghemat uang, bukan untuk menghabiskannya. Tahap ketiga, proses-proses konsumsi dikaitkan dengan hubungan-hubungan sosial nyata dan ideal yang membentuk dunia pembelanja. Dalam tahap ini khususnya, konsumen tipikal yang terkait dengan salah satu gender membeli merek atau rasa tertentu sehubungan dengan pemahamannya tentang bukan hanya soal kebutuhan semata-mata, melainkan pemikirannya tentang apa yang akan meningkatkan kualitasnya sebagai individu. Miller
18
menyimpulkan bahwa „tujuan primer dibalik shopping bukanlah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan melainkan usaha untuk berhubungan dengan subjek-subjek yang menghendaki barang-barang itu.
Ritzer (2011) mengidentifikasikan perubahan; pertama, dari pada harus pergi ke banyak lokasi yang berbeda, tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan (shopping mall) dan pusat belanja besar (mega mall) (juga took pangan serba ada dan took serba ada raksasa) telah memungkinkan adanya „one-stop shopping, belanja apa saja di satu tempat. Banyak katedral konsumsi (seperti mega-mall, Disney World, kapal pesiar, Las Vegas dengan kasino-hotelnya) dengan segenap keistimewaannya telah menjadi „tempat tujuan‟ dan orang-orang yang mendatanginya untuk mengkonsumsi tempat-tempat itu seperti halnya mereka mengonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan di sana. Ketiga, bukannya menyuruh pelayan melayani konsumen, kini banyak konsumsi yang mengharuskan konsumen melakukan swalayan, tanpa dibayar. Pada akhirnya katedral-katedral konsumsi mengubah relasi sosial sedemikian rupa sehingga konsumen lebih banyak berinteraksi dengan tempat dan yang ditawarkan tempat itu, bukan dengan orang yang bekerja disana atau dengan sesama konsumen.
Konsumsi adalah sebuah perilaku aktif dan kolektif, ia merupakan sebuah paksaan, sebuah moral, konsumsi adalah sebuah institusi. Ia adalah keseluruhan nilai, istilah ini berimplikasi sebagai fungsi integrasi kelompok dan integrasi kontrol sosial. Masyarakat konsumsi, juga merupakan masyarakat pembelajaran konsumsi, pelatihan sosial dalam konsumsi, artinya sebuah cara baru dan spesifik
19
bersosialisasi dalam hubungannya dengan munculnya kekuatan-kekuatan produktif baru dan Restrukturisasi monopolistik sistem ekonomi pada produktivitas yang tinggi (Ritzer. 2011).
Semua ideologi konsumsi ingin meyakinkan kita bahwa kita telah memasuki era baru dan sebuah revolusi kemanusiaan yang menentukan, yang memisahkan zaman yang menyedihkan dan Heroik terhadap produksi dengan zaman eforis konsumsi, dimana ia telah mengembalikan hak pada manusia dan pada keinginannya. Konsumsi tampak berlawanan dengan ideologi nyata, sebagai suatu dimensi paksaan yang: (1) Didominasi oleh paksaan arti, pada tingkat analisis Struktural (2) didominasi oleh paksaan produksi dalam analisis strategis (sosio-ekonomi-politik). “Thrift is unamericain,” kata White “berhemat berarti anti Amerika”(Ritzer. 2011). Semoga kita tercerahkan.
20
Pierre Bourdieu; Menyikap Kuasa Simbolik M. Chairul Basrun Umanailo
Pada umumnya kalangan akademisi, peneliti hingga mahasiswa Sosiologi cukup Familiar dengan nama seorang “strukturalisme konstruktivis” asal Prancis yang bernama Pierre Bourdiue, yang dikenal lewat konsep Habitusnya. Bourdieu sendiri berpendapat, bahwa Sosiologi tidak hanya harus mengkaji kehidupan sosial melalui konsep struktur sosial, melainkan yang terpenting justru memperhatikan tindakan sosial individu dan makna antar subjektif.
Dalam buku Pierre Bourdieu menyingkap kuasa simbol, penulis mencoba untuk lebih jauh mengeksplorasi sistem simbol dalam mengkonstruksi realitas. Buku ini juga berupaya menyajikan penafsiran dan pemahaman tentang kuasa simbolik menurut pemikiran Pierre Bourdieu. Penyajian yang diberikan dalam konstruksi buku menyerupai proses dialog antara penulis dengan diri Bourdieu yang dimengerti dalam arti luas baik latar kebudayaannya, lintasan sejarah, dan lingkungan yang berada disekelilingnya. Memang tidaklah mudah untuk memahami ruang gerak pemikiran Bourdieu dengan
21
sirkulasi pemikiran yang begitu luas dalam mengkaji setiap realitas.
Dalam teks yang tersusun dalam buku ini, Bourdieu membuktikan kalau selera manusia tidaklah netral, tetapi selalu terkait dengan citra sosial tertentu. Termasuk halnya bahasa dimana penggunaannya bersifat menular dari kelas atau kelompok sosial yang satu ke lain. Termasuk anggapan bahwa semakin hegemonik kekuasaan beroperasi, makin efektif pula bahasa yang ditularkan kepada mereka yang lemah. Bahasa memiliki keterkaitan dengan arena pertarungan kekuasaan. ia bisa bertujuan sebagai alat kekuasaan dan juga untuk melestarikan kekuasaan. Seperti halnya kekuasaan simbolik sebagai kekuasaan tak tampak dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan.
Buku yang terdiri dari lima bab tersebut, secara umum mendiskripsikan; Pertama, pertautan kekuasaan dan kekerasan dalam tata simbol. Kedua, trajektori kehidupan dan proyek pemikiran. Ketiga, Bahasa, pertarungan kekuasaan, dan kekerasan simbolik. Keempat, tata wacana neoliberalisme dan yang kelima, catatan kritis Bourdieu tentang praktik dominasi dalam tata simbol. Secara keseluruhan merupakan suatu kerangka pemikiran besar yang mengeksplorasi kuasaan simbol dalam mengkonstruksi realitas.
Pada umumnya, kajian Bourdieu masih berkutat pada konsep-konsep seperti halnya Habitus, capital, field, dan pendekatan interpretatif simbolik, namun yang menarik dalam buku ini adalah “bahasa” kemudian dijadikan ranah pertarungan, yang oleh penulis dilihat dari sudut pandang simbol dan mempertautkan dengan isu kekuasaan. Maka simbol akan bekerja sebagai indeks kekuasaan bagi kelas yang mendominasi dan didominasi. Tidak heran jika
22
kemudian banyak kajian dalam buku ini dianggap relevan dengan kondisi bangsa Indonesia.
Tidak mudah untuk menelaah pemikiran-pemikiran Bourdie yang bernuansa meta-teori, pembaca dituntut untuk memiliki nalar konstruktif dalam memahami realitas dan itulah ciri khas dari seorang Bourdieu. Baginya teks haruslah menjadi tindakan, tidak memisahkan teori dan praktik pada ranah yang berbeda seperti kritiknya terhadap pengagum Hegel agar dalam pemikirannya “diberikan kaki” sebagai simbol bahwa teori harus berdiri di atas realitas. Sebuah teori bukan sekedar menjelaskan melainkan juga mengubah tatanan sosial ekonomi yang tidak adil.
Ada kemudahan-kemudahan untuk memahami penyampaian isi buku pada pembaca, seperti kemudahan kita memahami pola berpikir Bourdiue yang masih terjebak pada konsepsi kekuasaan, penguasaan, dan yang dikuasai. Alur berpikir yang sederhana tersebut terkadang membuat pembaca yang telah menguasai konstruksi berpikir Bourdiue lebih memilih ilustrasi penulisan ketimbang konsep yang diberikan oleh Bourdieu di dalam buku ini, karena dianggap bukanlah sesuatu yang terbarukan lagi.
Oleh penulis, konstruksi pembahasan coba dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, ini cukup menarik bagi pembaca pemula namun bagi mereka yang memiliki konstruksi berpikir sendiri akan kembali bertanya tentang Determinasi peran simbol terhadap aktor, dan konteks ini yang selalu menjadi kelemahan Bourdieu yang semakin jauh meninggalkan subjektifitas.
Di akhir penulisan, Bourdieu sendiri dikritik telah menggunakan kekerasan simbolik dalam gagasan-gagasannya, seperti habitus dan field. Ide-ide yang ia ciptakan dianggap sebagai praktik kekerasan simbolik
23
yang sedang dijalaninya. Bourdieu dinilai sedang mempresentasikan gagasannya ke dalam simbol-simbol yang ujungnya untuk memperoleh pengakuan bahwa gagasan yang ia produksi sebagai sesuatu legitimasi.
Dan akhirnya, kita sebagai pembaca akan menentukan sendiri dimana letak titik kritis buku ini, kita bisa melihat serangkaian pemikiran dan perbandingan fenomena sebagai alur cerita yang akan kita akhiri dengan pertanyaan, Apa benar kita telah terperangkap dalam kuasa simbol yang disampaikan oleh penulis?
24
Perang Itu Belum Usai Tri Yatno
Kekuasaan kadang membuat kita lupa diri, khilaf
bahkan kita mampu berbuat apa saja untuk suatu yang
namanya kekuasaan. ada apa yang keliru sehingga senayan
kembali harus terjadi hiruk pikuk. perebutan kursi pimpinan
komisi semakin bordering nyaring, dengan tidak tersedianya
porsi kursi pimpinan bagi mereka yang tergabung pada
koalisi Indonesia hebat. penyebab utama yang dituduhkan
adalah Hegemoni dan Dominasi politik yang dilakukan oleh
koalisi merah putih terhadap kehidupan berpolitik di dewan
perwakilan rakyat Indonesia yang kita kenal dengan nama
DPR-RI.
Musabab dari itu semua, karena Undang-Undang yang
di simbolkan “MD3” yang mengisyaratkan pimpinan yang
berbentuk paket tidak terpisahkan antara ketua dan ketiga
wakil ketua sehingga dengan Representatif 5 fraksi sudah
dipastikan koalisi merah putih akan menyapu bersih seluruh
kursi pimpinan yang berada di DPR. Dilain pihak dengan
keterbatasan pemenuhan syarat dan kelemahan dalam
komunikasi politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mencoba
untuk membuat trik dan intrik agar supaya keinginan mereka
cukup terakomodir. apa yang akan kita perdebatkan adalah
politik subtansif dan politik formalistis.
Ketika bicara tentang politik subtasif di DPR maka
selayaknya lembaga DPR merupakan lembaga politik yang
mana setiap individu maupun kelompok akan berusaha untuk
merebut dan mempertahankan kekuasaan kalau
disederhanakan maka akan menjadi manajemen kekuasaan.
jadi apapun yang dilakuka oleh kelompok merah putih bukan
menjadi masalah ketika trik dan intrik politiknya memang
sesuai unsur dalam berpolitik. kita tidak serta-merta
menyalahkan bahkan mengasumsi bahwa telah terjadi
25
polarisasi kekuasaan berdasarkan kelompok kepentingan
namun mestinya ini semua dilihat sebagai suatu seni
berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.
Sementara ketika koalisi Indonesia hebat mengkritik
keras apa yang terjadi, maka logika yang dipakai adalah
politik formalis, dipaksakan untuk unsur keterwakilan harus
diadakan, bahwa DPR tidak semetinya dikuasai oleh satu
kelompok kepentingan dan ini menyalahi aturan tata tertib
yang notabene masih bersifat normative. kesimpulan
sederhana bagi realitas politik yang ada bahwa ketika
kekuasaan seseorang atau kelompok terhambat maka akan
ada dua cara untuk menghancurkan hambatan tersebut, yaitu
dengan mengganggap apa yang terjadi sebagai
Inskonstitusional serta melibatkan unsur media untuk
mencitrakan sebagai fenomena negative.
Bagi saya, kondisi seperti ini jelas sudah terbaca dari
awal. politisi kita adalah politisi dadakan, tidak ada pola
perencanaan politik yang matang ketika mengerti bahwa
kekuatan mereka terbatas dan akhirnya ideology di tunggangi
prinsip-prinsip Demokrasi di perkosa. semua partai berteriak
bahwa musyawarah untuk mufakat, setiap orang
menginginkan politik yang santun tapi semua yang mereka
inginkan tidak diseimbangkan dengan perilaku politik yang
cerdas. maka pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan
kembali harus terjadi.
26
Ada segregasi pola politik yang berpotensi akan
menghancurkan seluruh tatanan perpolitikan kita; pertama;
ketika etika politik dipakai untuk memaksa formalitas politik
maka akan lahir “penipu politik” yang mana akan kita lihat
lima tahun kedepan bahwasanya pencitraan tidak akan
sanggup menyelesaikan persoalan negara dengan sekedar
“blusukan” atau dengan istilah saya “Asal bapak kelihatan”.
yang kedua pemaksaan prinsip politik yang dipaksakan pakai
untuk memaksa politik subtansi maka akan lahir yang sering
kita takutkan bersama yaitu transaksi politik, dimana
keterlekatan menjadi pedoman untuk bertindak dalam
berpolitik, alhasil seperti yang dimainkan oleh kelompok
merah putih.
Tidak perlu kita risaukan, sebab setiap perhitungan-
perhitungan tindakan jelas sudah di hitung pula
konsekuensinya. antara kedua hal tersebut masing-masing
memiliki kelemahan yang tentunya akan mendominasi dari
setiap tindakan yang diambil. kembali lagi pada perang yang
belum usai, maka bagi saya adalah situasi ini memaksa kita
terpolarisasi pada penguasa Eksekutif dan penguasa
Legislative. Pada trial politika ini masih bisa dianggap suatu
kebenaran namun pada dual politika ini merupakan perang
yang tiada habisnya. drama ini selesai ketika ada kelompok
yang terputus kesadarannya bahwa dia harus bermain pada
ranah subtansif ataukan formalitas dan haruskah saya
bertindak sebagai penipu politik ataukah makelar transaksi
untuk sebuah benda yang teramat abstrak yaitu
“KEKUASAAN”.
27
TRAGEDI KABINET KERJA JOKOWI
M. Chairul Basrun Umanailo Minggu 26 Oktober 2014,
Presiden terpilih Joko Widodo memperkenalkan para menteri
yang rencananya akan dilantik pada senin pagi di istana negara.
jokowi bukan orang baru dalam menciptakan drama-drama
politik yang luar biasa hingga mampu menciptakan eskalasi
ekspetasi yang luar biasa terhadap dirinya. para menteri yang
diperkenalkan adalah mereka yang lewat pergunjingan panjang
antara publik, tim transisi sampai ketua parpol koalisi sampai-
sampai mengkhawatirkan masyarakat. dibalik semua itu ada
beberapa fenomena dan intrik politik yang bisa kita kaji secara
Sosiologis bahwasanya kembali Jokowi selalu memakai simbol
sebagai proses pencitraan terhadap keberlangsungan kehidupan
politiknya.
Kemeja putih sebagai simbol pemaknaan kesucian
menjadi Trend baru dalam bentukan kabinet yang dibangun atas
pondasi kerja keras yang dikendaki oleh sang Presiden. Satu
persatu kemudian para menteri diperkenalkan kepada publik,
entah apa maksudnya yang jelas Jokowi menggeser tradisi yang
sakral menjadi begitu elegan dan seperti halnya menabrak
dinding formalitas yang terpasung di Istana negara selama ini.
Nama-nama yang dipanggil adalah mereka yang bagi saya
28
sendiri merupakan hasil Mapping politik yang dilakukan oleh
koalisi Indonesia Hebat, seperti ini gambaran yang bisa saya
sampaikan;
- 30 % untuk partai pendukung koalisi
- 30 % untuk professional murni
- 30 % untuk professional yang terafiliasi
- 10 % untuk tim Yusuf Kalla
Apapun yang terjadi, struktur bangunan politik harus
mendapat dukungan dari koalisi, sebab ada beberapa agenda
yang mestinya harus mendapatkan dukungan yang besar dari
partai pendukung. hal selanjutnya yang menarik dari
pengumuman para calon Menteri sepertinya pada acara-acara
penganugrahan yang seringkali tampil di layar televisi kita.
Bagi sebagian orang hal ini dianggap berlebihan dan kurang
produkstif karena lebih mengemukakan sensasi dari pada
subtansi dari sebuah perkenalan. apa yang dikehendaki, lagi-
lagi hanya Jokowi yang tahu.
Mengemukakan calon Menteri bagi Jokowi dan Yusuf
kalla bukanlah pekerjaan yang mudah, ada usaha untuk
kemudian memilih rekan kerja yang memiliki kredibilitas yang
luar biasa dan terlebih lagi yaitu mereka yang harus bersih dari
korupsi dan tidak akan korupsi, maka di ajukanlah nama-nama
yang akan menjadi menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi
dan PPATK. apa maksud dibalik semua itu, bukankah kita
memiliki jaksa Agung atau juga dengan Mahkamah Agung, apa
kemudian ini bukan suatu pelecehan karena Presiden lebih
percaya pada lembaga Ad-hoc ketimbang lembaga negara.
kalaupun itu hak preogratifnya presiden tapi harus ada etika
politik yang dimainkan oleh presiden. Jangan sampai KPK
hanya sebagai lahan cuci tangan ketika desakan dari koalisi
untuk posisi menteri membuat sang presiden semakin
kebingungan. Ada perkembangan persepsi bahwasanya Jokowi
tidak mampu melawan Megawati dan kelompok PDI-P
sehingga bermain dengan citra KPK sebagai lembaga yang lagi
ngetrend sebagai sang pemberantas korupsi. ahk,,, lagi-lagi saya
29
harus bersabar, inilah yang saya sebut dengan pengembirian
lembaga pemberantas korupsi.
Statmen apapun yang akan kita ajukan tentunya bukan
yang terbaik untuk perubahan tapi paling tidak kita inginkan
perubahan itu bisa terjadi. Jokowi dengan segala intrik politik
yang menyerupai drama, sangat membuat saya kagum terlebih
ketika memutuskan untuk penyusunan kabinet akan didomonasi
oleh professional, namun alangkah kagetnya ketika semua itu
terjawab, yang jelas istilah “tidak ada makan siang gratis” sudah
terakomodir dalam pikiran Jokowi, jadi persetan dengan janji
dan pengharapan yang pernah terucap disaat kampanye politik.
inilah yang saya sebut dengan “tragedi” kabinet kerja, karena
orang yang tersusun adalah hasil tekanan ditambah ancaman
dan lebih parahnya lagi ditambah dengan “sok tau” nya sang
presiden. semoga Indonesia masih terus hebat seperti yang
diharapkan…. Amin.
30
MEMAHAMI KONTUR KONFLIK PADA CYBER COMMUNITY
Tri Yatno
Perubahan yang terjadi dimasyarakat, sebuah
konsekuensi dari kemajuan teknologi dibidang informasi dan
komunikasi, khususnya perubahan terhadap aspek
komunikasi, dimana interaksi yang terjadi antar manusia,
makin membentang luas. Kehadiran internet, yang dianggap
sebagai penemuan terbesar abad ini, semakin menegaskan
bahwa dunia tidak lagi terbagi dalam sekat-sekat geografis
ataupun teritorial yang membatasi ruang. Dunia saat ini,
seperti apa yang diramalkan oleh Marshall McLuhan dalam
pemikirannya yang tertuang dalam buku “Understanding
Media” (1964) sebagai kampung Global (Global Village),
dimana masyarakat berinteraksi dan dibentuk oleh teknologi
elektronik didunia yang semakin mengerut ( Bungin, 2005 ).
31
Secara harfiah, Internet – interconnected networking
merupakan suatu jejaring komputer yang terhubung dengan
beberapa jejaring komputer lainnya. Menurut Castells, dalam
Ritzer, 2011 menyatakan bahwa fungsi dan proses dominan
dalam abad informasi semakin tertata diseputar jaringan,
yang didefinisikan sebagai perangkat node yang saling
terhubung.
Sementara Pierre Levy dalam bukunya “Cyber
culture“, (Littlejohn, 2009) memandang bahwa Word Wide
Web sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka,
fleksibel, dan dinamis, yang memungkinkan manusia
mengembangkan orientasi pengetahuan baru.
Benar apa yang diramalkan dahulu oleh McLuhan,
seperti dikatakan dalam bukunya “Understanding the media”,
bagaimana komunikasi elektronik bakal mengubah cara kita
memandang diri kita sendiri dan dunia kita. Kini teknologi
telah memperpendek jarak, mempercepat komunikasi, dan
memberikan kita sebuah dunia yang jauh berbeda dari yang
dialami generasi sebelumnnya. Pola kehidupan masyarakat
manusia khususnya pada aspek interaksi sosial diantara
mereka ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi
yang dikuasai masyarakat bersangkutan. All technology is
Communication, yakni perpanjangan (ekstensi) dari diri kita
yang memungkinkan kita untuk mencapai lebih lanjut
melampaui ruang dan waktu.
Pengorbanan kita dalam membuat peningkatan ini
tanpa disadari telah mengamputasi diri kita sendiri. "Setiap
teknologi baru memerlukan perang baru, "kata McLuhan
Sekarang begitu banyak pengguna teknologi internet yang
bermetamorphosis dalam berbagai komunitas maya berupa
Mailing list, Newsgroup atau Bulletin board, diantara
semuanya menyediakan ruang dialog, debat, bahkan transaksi
jual beli (e-Commerse). Sehingga apa yang dikatakan
Marshall McLuhan (1964) mengenai „global village‟ hampir
dikatakan benar-benar terwujud sekarang ini. Aktifitas
berkumpul sekelompok orang yang disatukan oleh minat atau
32
ketertarikan kemudian menciptakan jalinan komunikasi yang
terpisahkan dari ruang-ruang dunia nyata (offline) namun
mampu menciptakan sebuah ruang sosial baru (social
spheres). Inilah media baru, inilah media siber.
MEMAHAMI CYBERSPACE
Disadari bahwa manusia kini berada dalam sebuah fase
cyber, dimana hampir semua aktiftasnya menggunakan Cyber
source dalam mencapai tujuannya. Komputer, jaringan internet,
telpon genggam dengan fasilitas data GPRS atau layanan pesan
singkat menjadi sesuatu yang sangat akrab dalam keseharian.
Beberapa aktifitas komunikasi yang dahulunya dilakukan
secara tatap muka dan melulu bertemu fisik, sekarang bisa
dilakukan hanya dengan memencet tombol keyboard komputer.
Tanpa disadari, masyarakat telah hidup dalam dua dunia
kehidupan yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan
masyarakat maya. Cyberspace menurut William Gibson,
Neuromancer, 1993 adalah
“Consensual hallucination experienced daily by billion
of legitimate operators, in every nation, by children
being taught mathematical consepts, a graphic
representation of data abstracted from banks of every
computer in the human system. Unthinksable
complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the
mind, clusters and constellations of data. Like city
lights, receding....”.
Komunikasi cyberspace, komunikasi berbasis komputer
yang menawarkan realitas yang berbentuk virtual (tidak
langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara virtual,
kita dapat merasa seolah-olah ada ditempat dimana kita
berinteraksi, dan dapat melakukan hal-hal yang dilakukan secara
nyata, sejatinya dalam komunikasi dimasyarakat nyata misalnya
transaksi dan berdiskusi. Substansi cyberspace sebenarnya
adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dalam
33
konteks ini, dilakukan secara elektronik dalam bentuk
visualisasi tatap muka interaktif. Komunikasi virtual itu,
dipahami sebagai virtual reality, yang sering dipahami sebagai
alam maya, kendati keberadaan sistem elektronik itu sendiri
adalah konkret dimana komunikasi virtual sebenarnya dilakukan
dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskrit.
SOCIAL NETWORK
Manusia secara kodratnya adalah makhluk pribadi dan
makhluk sosial, dimana kendati manusia memiliki ego pribadi
untuk memenuhi kebutuhan, namun manusia sadar dalam
pemenuhannya membutuhkan orang lain. Kebutuhan itulah,
yang kemudian membuat setiap manusia saban melakukan
interaksi, menjalin relasi sosial dengan orang lain. Relasi yang
bermula berdasarkan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan
pribadi, lambat laun akan berkembang relasi sosial dalam
bentuk pertemanan, atau kekerabatan, bahkan persaudaraan
dalam memenuhi kebutuhan kelompok dalam lingkup yang
lebih besar.
Namun dalam proses pemenuhan kebutuhan dalam
masyarakat nyata itu, sering menimbulkan konflik sosial,
ekonomi, dan politik. Perebutan terhadap space atau ruang dan
territorial dalam masyarakat nyata, sering kali dipicu persoalan
perbedaan ras, gender, diskriminasi suku, warna kulit, dan
agama. Terbentuknya kelas-kelas sosial (kelas, status, prestise)
dalam masyarakat nyatapun, sebagai penyebab matinya makna
kebebasan dan demokrasi.
Dalam masyarakat nyata, seringkali kekuasaan
mendominasi apa yang dimaksud kebebasan dan demokrasi,
seolah kebebasan dan demokrasi milik penguasa, yang kerap
menekan setiap individu yang ada dalam komunitas tertentu.
Munculnya persoalan dalam masyarakat nyata itu, yang
kemudian dieliminasi oleh interaksi dan komunikasi dalam
masyarakat maya (Cyberspace) melalui media internet, menjadi
alasan utama masyarakat mulai beralih. Perubahan cara
masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi inilah, menurut
34
Carey, 2003 dalam McQuail menyatakan seiring dengan
teknologi berbasis komputer, terdapat pula berbagai inovasi
yang dalam beberapa hal mengubah aspek komunikasi. Inilah
faktanya, internet telah menciptakan lingkungan informasi yang
terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia
mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru melalui dunia
tidak nyata atau dunia maya.
CYBER COMMUNITY
Cyberspace atau dunia maya kini menjadi “ruang baru
“tempat bermain dengan berbagai aspek Immanterial manusia
yang tidak diberi tempat didalam dunia nyata. Didalam
Cyberspace berbagai pikiran saling bertemu tanpa tubuh/ fisik
(tubuh, diri, identitas artifisial). Alasan utama, masyarakat kini
memanfaatkan interaksi melalui Cyberspace atau dunia maya
melalui media internet mampu menciptakan semacam
komunitas ideal, yang melampui keterbatasan dan terbebas dari
berbagai perbedaan gender, ras, warna kulit, dan agama.
Masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya
mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam
kehidupan kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota
masyarakat maya.
Dipastikan bahwa konstruksi masyarakat maya pada
mulanya berkembang dari sistem intra dan antar jaringan yang
berkembang menggunakan sistem sarang laba-laba sehingga
membentuk sebuah jaringan masyarakat yang besar. Dunia
maya pun bertranformasi menjadi sebuah dunia virtual, dimana
anggota jaringan membentuk masyarakat virtual/ tidak nyata,
memiliki faktor pengikat yang cukup kuat. masyarakat maya
(cyber community) terbentuk dari sebuah komunal anggota
jaringan yang terjalin atas motif tertentu (Ananda Mitra, 2010).
Motif itu bisa jadi hobi, cara pandang, kesamaan latar belakang
(pendidikan, budaya, agama, profesi atau sebagainya).
Pembentukan komunitas maya itupun, terjadi pada
pembentukan komunitas nyata. Dimana masyarakat nyata
membentuk organisasi dilatar belakangi hal yang serupa.
35
Namun identitas pribadi setiap anggota komunitas maya
terwakilkan oleh tampilan tekstual, gambar, atau ikon lainnya
yang terlihat dalam dunia virtual. (Ananda Mitra, 2010).
Identitas inilah yang menjadi simbol penghubung dalam
membentuk relasi. Proses komunikasi komunitas maya yang
terjadi terus menerus mampu melahirkan kebutuhan “ditemani”
saat mereka sendiri atau kesepian (Ananda Mitra, 2010).
Artinya cyberspace mampu menciptakan budaya instan yang
adiktif dalam kehidupan manusia. Semakin interaktif sebuah
media, sejatinya memungkinkan adanya motivasi dan respon
secara berkesinambungan dari para pengguna. (McQuail, 2011).
Banyak hal yang bisa kita peroleh dengan sangat mudah dalam
cyberspace.
Kemampuan yang dikembangkan dalam
cybercommunity itu, sejatinya sebuah potensi yang dimiliki,
dimana cyberspace menciptakan kebahagiaan hidup bukan
lewat benda-benda materi tetapi lewat benda-benda virtual.
Bahkan cyberspace memiliki potensi menciptakan semacam
“gaya hidup artificial” dan “egalitanan” yang tidak dikungkung
oleh kepemilikan ruang, benda materi, sebab apa yang disebut
place, ruang, dan gaya hidup, didalam dunia materi tidak lagi
bermakna didalam cyberspace.
CYBER COMMUNITY DI INDONESIA
Di Indonesia, kekuatan media internet dalam proses
proses interaksi cybercommunity, adalah munculnya media
sosial yang lahir sejak 5-10 tahun belakangan. Media sosial itu
seperti facebook, google+, twitter, foursquare, flickr, kaskus
yang merupakan sebuah parameter kemajuan teknologi yang
diiringi perilaku sosial terhadap sesamanya untuk melakukan
interaksi. Melalui media sosial ini, keterbatasan ruang dan
waktu seseorang untuk melakukan interkasi dengan sesama,
teratasi. Dengan media sosial ini, manusia tidak hanya dapat
berbagi dilingkungan terdekat mereka, tetapi dapat berbagai
keberbagai penjuru dunia. Tahun 2009, 40 juta orang Indonesia
tercatat sebagai pengguna internet. Laporan ini, merupakan data
36
pengguna internet paling tinggi diantara negara Asia Tenggara
(Atwar Bajari, 2011).
Asosiasi Penyelenggara jasa Internet indonesia atau
APJII, Pemerintah memprediksi tahun 2015, pengguna internet
ditanah air diharapkan mencapai 50% dari jumlah penduduk
yang diperkirakan berjumlah 240 juta jiwa. APJII pun melansir
jumlah pengguna internet, rata-rata diperkotaan mencapai 60%
adalah usia dibawah 30-an. Internet mengkonstruksi dunia maya
menjadi dunia tanpa batas, dunia kebebasan, yang bisa dimasuki
dan dimanfaatkan oleh siapapun. Manusia yang
menggunakannya disediakan ruang yang sebebas-bebasnya.
Internet menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan
antara lain words wide web (www), elektronik mail (e-mail),
mailing list, file transfer protocal (FTP), news group, chat
group, situs networking, dan lain-lain. Dalam komunitas ini,
pengguna internet dapat berkomunikasi, mencari informasi,
berbelanja, serta transaksi bisnis lainnya. Karena sifat internet
yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, maka internet sering
disebut dengan Cyberspace atau Virtual Word (dunia maya).
Salah satu kasus yang muncul sebagai aflikasi
cybercommunity adalah terbongkarnya sindikat bisnis percaloan
pekerja seks komersial (PSK) via media sosial-facebook via
internet dengan 1600 PSK pengguna jasa “marketing Lendir”
skala nasional. Pelaku bisnis esek-esek itu, hanyalah seorang
perempuan cantik, Yunita alias Keyko, yang mampu membuat
jaringan media sosial untuk menawarkan dan menerima order
dari para pelanggan yang membutuhkan layanan “Plus-Plus”
Foto dan data diri singkat anak buahnya itu dikirim ke sejumlah
lalki-laki “hidung belang” melalui ponsel Blackberry. Uniknya
meski Yunita memiliki anak buah cukup banyak, namun Yunita
tidak mengenal satupun anak buahnya. Ia hanya mengendalikan
melalui 300 mucikari yang juga anak buahnya.
37
CYBER CULTURE
“Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan
masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”
(Koentjaraningrat, 2000 : 180). Budaya atau kebudayaan tidak
hanya terbatas pada hal-hal yang mengandung unsur kesenian,
adat, dan etnik saja. Segala bentuk pola perilaku atau tindakan
manusia adalah kebudayaan. Segala bentuk pola perilaku atau
tindakan mulai dari berpikir, mengamati, bekerja, berjalan,
hingga cara makanpun merupakan sesuatu yang dapat dikatakan
sebagai budaya. Hal itu dikarenakan kemampuan untuk
melaksanakan semua sistem tindakan itu tidak terkandung
dalam gen manusia yang dibawanya sejak lahir atau dengan
kata lain semua kemampuan tersebut bukan merupakan sesuatu
yang begitu saja ada dan terjadi dengan sendirinya. Berbagai
sistem tindakan tersebut ada dan terjadi karena dibiasakan oleh
manusia dengan belajar. “Budaya menjadi semacam alat bantu
bagi menusia dalam menjalani kehidupannya” (Kluckhohn
1941, dalam suaraputu.com). Sehingga kehidupan manusia dan
kebudayaannya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Begitu juga dengan sikap manusia dalam melihat,
memaknai, dan memahami sesuatu baik yang bersifat lama,
baru, konvensional, maupun modern akan sangat dipengaruhi
oleh budaya yang telah menjadi konsep dalam diri manusia itu
sendiri. Dunia cyber dalam kaitannya dengan budaya
masyarakat kita merupakan suatu bentuk fenomena yang masih
dilihat sebagai pernyataan baru di kalangan masyarakat.
Di dunia yang meliputi berbagai infrastruktur teknologi
komunikasi dengan jaringan internet sebagai media utamanya
ini, tentu juga terdapat berbagai sistem tindakan yang telah
menjadi suatu budaya serta memiliki peran layaknya sebagai
syarat untuk bertahan dalam kehidupan dunia cyber. Berbagai
interaksi yang terjadi di dunia cyber memungkinkan untuk
terbentuknya system kesatuan manusia yang dikenal dengan
sebutan masyarakat cyber (cyber community), dimana aplikasi
utama yang digunakan oleh para pengguna internet ternyata
38
adalah untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi antara
pengguna internet ( Purbo, 2003 : 27 ). Budaya siber menjadi
sebuah fakta. Fakta tersebut ditandai terbentuknya berbagai
komunitas di dunia cyber dengan interaksi yang terjadi memiliki
bermacam-macam kepentingan dan hal-hal yang menarik
tentunya. Media baru dan budaya siber kini telah menghadirkan
berbagai informasi serta berkembang menjadi sebuah kultur
baru didunia online. Menjadi sebuah Fenomena baru dengan
munculnya budaya cyber tersebut dapat dilihat dengan hadirnya
sosial media, facebook, tweeter, flicker, skype, media kaskus
dan berbagai online culture media seperti Blogs, Bulletin Board
Systems, Chat, E-Commerce, Games, Peer-to-peer Social
networks, Usenet, Virtual worlds dan sebagainya menjadikan
pola kehidupan masyarakat dunia kini telah berubah. Pramod K.
Nayar.
Melalui bukunya “The New Media and Cyberculture
Anthology”, telah banyak menguraikan tema-tema sosial
kontemporer yang berkaitan dengan media cyber. Beliau
membahas dalam era new media tentang topik-topik seperti
ekonomi, geografi, ketenaga kerjaan, kesehatan, game
komputer, bentuk dan identitas gender dan rasial dari
cybercultures serta seksualitas. . Kajian utama Nayar adalah
bahwa cybercultures, telah membuat tatanan sosial meng-global
dan bukan untuk mengisolasi diri seseorang dalam ruang
komputer. Soal cyberculture adalah soal bagaimana teknologi
dilihat secara kontekstual dalam mempengaruhi kehidupan
sosial sebagai bagian budaya teknologi.
Yang menarik ketika masyarakat sudah memiliki
ketergantungan dengan media yang menjadikan mereka lebih
banyak beraktifitas sosial disana adalah pada waktu munculnya
konflik. Contoh kecil yang bisa di kaji adalah konflik antara
individu, Dewi Persik dengan Ian Kasela dimana keduanya
lebih banyak melakukan aktifitas interaksi melalui media sosial
yang lebih dikenal dengan nama Twitter. Dewi Persik dengan
ketersinggungannya dengan apa yang di sampaikan oleh Ian
Kasela lewat akun Twitter nya sehingga dia juga ikut membalas
39
melalui akun twitter yang dimilikinya. Apa yang kemudian
terjadi selanjutnya, konflik yang diakibatkan oleh perbedaan
pandangan, pola pikir, tingkah laku kemudian berkembang ke
dunia cyber sehingga menjadi konsumsi publik. Dewi maupun
Ian tidak dapat membendung setiap dukungan yang datang dari
masing-masing kelompok mereka yang kebanyakan merupakan
penggemar atau mereka yang mengidolakan. Kondisi seperti ini
berkembang dan melibatkan banyak pihak dan terjadi dalam
sebuah ruang publik dimana setiap orang dari berbagai
komunitas dapat mengakses konflik yang terjadi tersebut.
Konflik tidak serta merta hanya dimiliki oleh individu yang
mengalaminya, pihak lain yang berada di luar mereka pun
punya kompetensi untuk ikut membesarkan atau
menyelesaiakan konflik yang terjadi.
Peranan media sebagai katalisator sangat berperan ketika
kedua belah pihak terus menerus berkonflik sehingga pada
sebuah titik tertentu kiranya dapat ditemukan penyelesaian.
Banyak kasus yang kemudian diselesaikan di luar media cyber.
Perdamaian antara mereka yang berkonflik lebih banyak terjadi
di luar media cyber, oleh karena intensitas serta efektifitas jauh
lebih mereka rasakan luas ketika bertemu langsung atau
memakai pihak ketiga. Jadi bila disimpulkan bahwasanya dunia
cyber tidak lebih dari pertautan serta aktualisasi wacana dari
masing-masing pihak yang berkonflik.
Apa sebab demikian, media cyber menyajikan pola
interaksi yang terbatas dengan jaringan yang luas. Jadi ketika
seseorang berkonflik dengan orang lain tidak perlu dengan
mengundang banyak orang untuk mendengarkan serta
memahami apa yang terjadi, namun lewat media yang tersedia
maka banyak orang kemudian bisa mengerti bahwa individu
tersebut sedang mengalami konflik dengan orang lain. Pada
akhirnya setiap individu akan merasa nyaman ketika konflik
yang mereka alami kemudian menjadi konsumsi orang banyak,
dengan konsekuensi sosial yang harus mereka tanggung apabila
kemudian konflik tersebut merugikan kemadaan mereka sendiri.
40
KONSUMERISME
M. Chairul Basrun Umanailo
Historisme
Memahami sebuah teori merupakan sebuah gambaran
umum yang harus kita telusuri hingga ditemukan titik awal
kelahirannya, begitu pula ketika memahami teori konsumsi
sebagai awal wacana konsumerisme, haruslah kita pahami
sebagai awal dari perkembangan manusia dalam
mengembakan pola pemenuhan kebutuhannya.
Sejak Revolusi Industri dan revolusi-revolusi abad ke
XIX, kebahagiaan memiliki arti dan fungsi ideologis maka
kebahagiaan harus terukur. Kebahagiaan bathiniah yang
terwujud melalui simbol maupun pemaknaan ditolak oleh
cita-cita konsumsi. Kebahagiaan didasarkan pada prinsip-
prinsip individualis dan diperkuat oleh Tables de Droits
deI‟Homme et de Citoyen (Daftar Hak-hak Manusia dan
Warga Negara) yang secara eksplisit mengenalkan kembali
hak kebahagiaan pada semua orang.
”Revolusi Kemapanan” (Baudrillard. 2013) adalah
pewaris dan pelaksana pesan-pesan Revolusi Borjuis yang
memiliki thesis implisit; semua orang sama di depan nilai
guna suatu objek dan barang (padahal objek dan barang
tidaksama dan terbagi di depan nilai tukar). Tiap orang juga
diberikan kebebasan yang sama untuk memiliki sumber-
41
sumber penghidupan yang pada akhirnya akan melahirkan
liberalisasi sistem pencapaian pemenuhan kebutuhan.
Istilah kelimpahruahan didefenisikan sebagai
keseimbangan produk manusia dantujuan manusia, orang-
orang primitif tidak mempunyai apa-apa sebagai milik
pribadi, mereka tidak dihantui oleh objeknya, yang mereka
pikirkan adalah bagaimana dapat berpindah ke tempat yang
lebih baik. Mereka sangat royal mengonsumsi sesuatu
langsunghabis tidak terhitung secara ekonomi (Baudrillard.
2013).
Kerobohan dan Keborosan kolektif, ciri
khasmasyarakat primitif merupakan tanda kelimparuahan
yang nyata. Bahwa segala sumberdaya yang dimiliki
merupakan suatu realitas keterhubungan antara manusia
dengan lingkungan. Mereka kemudian tidak tertantang untuk
mempertahankan, sebab bagi mereka hanya ekploitasi
sumber yang dianggap melampaui apa yang mereka
butuhkan, tidak perludi perbaharui, cukup mengambil hasil
dan berpindah pada situs baru yang lebih memiliki sumber
daya yang banyak.
Logika Dasar
Konsumsi diartikulasikan dalam rangkaian yang
merupakan urutan mitologi darisebuah cerita; manusia yang
memiliki kebutuhan-kebutuhan yang banyak menuju pada
objek yang memberinya kepuasan. Karena bagaimanapun
juga manusia itu tidak pernah merasa puas, cerita yang sama
terulang terus dengan kenyataan yang sudah hilang dari
cerita-cerita kuno. Manusia adalah mahluk individu yang
mempunyai kebutuhan yang dibawa untuk dipuaskan, juga
bukan karena konsumen ialah mahluk yang bebas, sadar
danseharusnya tahu apa yang dia inginkan.
Tujuan ekonomi bukanlah memaksimalkan produk
untuk individu, tetapi maksimalisasi produk yang
berhubungan dengan sistem nilai masyarakat. Konsumsi
42
adalah sebuah perilaku aktif dan kolektif, ia merupakan
sebuah paksaan, sebuah moral.
Konsumsi adalah sebuah institusi. Ia adalah
keseluruhan nilai, istilah ini berimplikasi sebagai fungsi
interasi kelompok dan integrasi kontrol sosial. Tujuan
konsumsi merupakan paksaan dan dilembagakan bukan
sebagai hak atau sebagai kesenangan, tetapi sebagai tugas
dari warnanegara (sebuah analisis struktural). (Baudrillard.
2013).
Semua ini merupakan konstruksi sosial atas realitas
ekonomi, seperti halnya sebuah Fakta Sosial yang bersifat
eksternal, dan memaksa. Kita semakin sulit menghindar
struktur nilai yang adaa pada masyarakat, ketika nilai itu
sudah terinternalisasi dalam suatu proses kehidupan sosial.
Jadi, bagaimana pun juga ada determinasi antara nilai
ekonomi yang memaksa serta penguasaan modal dan
kekuasaan atas logika dasar tujuan ekonomi.
Kita bisa mengikuti aturan sejarah sistem industrial
silsilah/asal usul konsumsi:
1. Tatanan produksi menghasilkan mesin/kekuatan
produktif, sistem teknik yang secararadikal berbeda
dengan alat tradisional.
2. Ia menghasilkan modal/kekuatan produktif yang masuk
akal, sistem investasi dan sirkulasi rasional yang secara
mendasar berbeda dengan kekayaan dan model
perdagangan sebelumnya.
3. Ia menghasilkan kekuatan tenaga kerja bergaji, kekuatan
produktif yang abstrak, tersistematisir, yang secara
mendasar berbeda dengan pekerjaan nyata dan dengan
pekerjaan tradisional.
4. Terakhir ia melahirkan kebutuhan-kebutuhan, sistem
kebutuhan, permintaan/kekuatan produktif sebagai
kumpulan yang dirasionalkan, disatukan, diawasi,
melengkapi tiga hal yang lain dalam proses pengawasan
total dengan kekuatan produktif dan dengan produksi.
(Baudrillard. 2013)
43
Semua ideologi konsumsi ingin meyakinkan kita
bahwa kita telah memasuki era barudan sebuah “revolusi”
kemanusiaan yang menentukan, yang memisahkan zaman
yang menyedihkan dan heroik terhadap produksi dengan
zaman eforis konsumsi, dimana ia telah mengembalikan hak
pada manusia dan pad keinginannya. Konsumsi adalah sistem
yang menjalankan urutan tanda-tanda dan penyatuan
kelompok. Jadi konsumsi itu sekaligussebuah moral (sebuah
sistem nilai ideologi) dan sistem komunikasi struktur
pertukaran. Menurut hipotesis ini, dan juga paradoks
mengenai hal itu munculnya konsumsi didefenisikan sebagai
kenikmatan yang ekslusif. Sebagai logika sosial, sistem
konsumsi didirikan atas dasar pengingkaran kenikmatan.
Disana kenikmatan tidak lagi muncul sama sekali sebagai
tujuan yang rasional, tetapi sebagai rasionalisasi individu
pada suatu proses yang bertujuan lain. Kenikmatan akan
memberi batasan konsumsi bagi dirinya, otonom dan akhir
konsumsi (Baudrillard. 2013).
Teori Konsumsi Mendeskripsikan konsumsi, berarti kita harus
melingkar pemahaman pada sebuah poros pertemuan antara
konsep ekonomi dan Perspektif Sosiologi. Ilmu ekonomi
klasik objek dari semua produksi konsumsi adalah konsumsi
dengan individu-individu yang memaksimalkan kepuasan
mereka melalui pembelian.
Horkheimer dan Adorno, misalnya berpendapat bahwa
logika komoditas yang sama serta perwujudan rasionalitas
instrumental dalam lingkup produksi tampak nyata dalam
lingkup konsumsi (Featherstone. 2008). Perilaku memenuhi
kepuasan dalam pola transaksi merupakan abstraksi rasio
manusia untuk memenuhi konsumsi yang dimaksud sebagai
suatu keinginan.
Pada tahun 1955, ekonom Victor Lebow menyatakan:
Tuntutan ekonomi sangat produktif kami bahwa kami
membuat konsumsi cara kita hidup, bahwa kita mengubah
44
pembelian dan penggunaan barang ke dalam ritual, bahwa
kita mencari kepuasan spiritual kita dan kepuasan konsumsi
ego kita. Kita perlu hal-hal yang dikonsumsi, dibakar,
dikenakan keluar, diganti dan dibuang pada tingkat yang
semakin meningkat (Lebow,2009).
J.F. Lyotard, dalam Libidinal Economy, mendeskripsi
bahwa teknologi berfungsi membebaskan hasrat dari segala
penghambat dorongan libido manusia. Ia memenuhi aktivitas
konsumsi manusia yang dapat melahirkan kesenangan dan
memberi kepastian.
Teknologi di sini tentunya tidak hanya terbatas pada
teknologi informasi dan digital saja, tetapi juga mencakup
hingga ke persoalan rekayasa desain arsitektural. Teknologi
dan idealisme desain arsitektural, terutama desain fasilitas
perbelanjaan. kini mulai dieksploitasi sebagai sarana bagi
akumulasi modal melalui pemenuhan hasrat konsumsi
(Yasraf, 2004). Werner Sombart, Emile Durkheim, dan
Thorstein Veblen, menyatakan bahwa konsumsi merupakan
kekuatan besar yang sangat menentukan di balik dinamika
dan struktursosial dalam sistem kapitalisme modern. Yang
lebih akhir, Anthony Giddens juga mengemukakan bahwa
budaya konsumerisme merupakan respon dan terapi terhadap
gejalakrisis identitas akibat pluralitas nilai dan pengetahuan
di dalam masyarakat post-tradisional.
Hingga kaum postmodernis seperti Jean Buadrillard juga
begitu menyadari fenomena inidengan pendekatan
semiotiknya terhadap budaya konsumerisme. (Trentman,
2004).
Menurut Baudrillard munculnya masyarakat konsumen
merupakan upaya mengorganisir kebutuhan masyarakat serta
mengintegrasikannya ke dalam sistem yang dirancang untuk
menggantikan semua interaksi terbuka antara kekuatan alam,
kebutuhan dan teknologi. Tekonologi menurut Jean
Baudrillard berperan penting, khususnya manusia sebagai
agen yang menyebar imaji-imaji kepada khalayak luas.
Keputusan setiap oranguntuk membeli atau tidak, benar-
45
benar dipengaruhi oleh kekuatan imaji tersebut.Konsumen
menurut Bauman adalah seseorang yang mengkonsumsi,
seperti makan, pakaian, kebutuhan bermain untuk memenuhi
kebutuhan atau keinginan seseorang. Dalam hal ini, uang
dalam banyak kasus berperan sebagai 'penengah' antara
keinginan dan kepuasan. Menjadi konsumen juga berarti
mengambil alih barang atau jasa untuk dikonsumsi. Mereka
membeli dan membayar sehingga mereka mempunyai hak
milik suatu barang atau jasa, dan bagi orang lain yang ingin
menggunakan harus minta ijin terhadap pemilik hak tersebut.
Menurut Bauman bahwa produsen/pekerja dinilai
sebagai sebuah estetika, namun konsumen justru sebaliknya.
Konsumen merupakan individu, soliter yang pada akhirnya
minim melakukan kegiatan; suatu kegiatan yang dipenuhi
dengan pendinginan dan membangkitkan, meredakan dan
mencambuk keinginan yang muncul sebagai sensasi pribadi,
dan tidak mudah menular. Tidak ada yang namanya
'konsumsi kolektif'. Memang pada kenyataannya ada
konsumen yang bisa mendapatkan kepuasan secara bersama-
sama, tetapi dikemudian hari muncul ketidak puasaan, karena
mereka mengkonsumsi hanya sebagai privasi dan
mendapatkan kesenangan (Bauman, 2005).
Lahirnya Konsumerisme
Werner Sombart, Emile Durkheim, dan Thorstein
Veblen, menyatakan bahwa konsumsi merupakan kekuatan
besar yang sangat menentukan di balik dinamika dan struktur
sosial dalam sistem kapitalisme modern. Yang lebih akhir,
Anthony Giddens juga mengemukakan bahwa budaya
konsumerisme merupakan respon dan terapi terhadap gejala
krisis identitas akibat pluralitas nilai dan pengetahuan
didalam masyarakat post-tradisional. Hingga kaum
postmodernis seperti Jean Buadrillard juga begitu menyadari
fenomena inidengan pendekatan semiotiknya terhadap
budaya konsumerisme (Trentman, 2004).
46
Budaya konsumerisme terutama muncul setelah masa
industrialisasi ketika barang-barang mulai diproduksi secara
massal sehingga membutuhkan konsumen lebih luas. Media
dalam hal ini menempati posisi strategis sekaligus
menentukan; yaitu sebagai medium yang menjembatani
produsen dengan masyarakat sebagai calon konsumen.
Menurut Werner Sombart, perkembangan ekonomi ditinjau
dari susunan organisasi dan idiologi masyarakat.Tahapan
pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart adalah
Zaman perekonomian tertutup, Zaman perekonomian
kerajinan dan pertukangan, Zaman perekonomian kapitalis
(Kapitalis Purba, Madya, Raya, dan Akhir). Karyanya ditulis
dalam sebuah buku yang berjudul Der Moderne Kapitalismus
(1927) (Bartholomew, 2001). Hidup manusia adalah proses
konsumsi, yakni masyarakat konsumen, artinya dimana
segala sesuatu dijual, dipertukarkan untuk hanya sekedar
memenuhi hasrat ingin memiliki suatu barang, tidak
terkecuali objek, pelayanan, tubuh, seks, kultur, ilmu
pengetahuan dan sebagainya, sebagaimana yang djelaskan
oleh Baudrillard (1972/1981: 147-148) yang dikutip oleh
Ritzer (Ritzer, 2003), Baudrillard memandang objek
konsumsi sebagai sesuatu “yang diorganisir oleh tatanan
produksi” atau dalam artian lain, kenyataanya kebutuhan dan
konsumsi adalah perluasan kekuatan produktif yang
diorganisir. Klaim sentral Baudrillard adalah bahwa objek
menjadi tanda (sign) dan nilainya ditentukan oleh sebuah
kode. Genosko, mendefenisikan kode sebagain sistem control
tanda. Artinya, “kode dalam pengertian yang lebih umum
merupakan sistem aturan-aturan guna menggabungkan
seperangkat terma yang stabil dalam pesan. Objek, dalam
masalah objek konsumsi ini, adalah bagian dari sistem tanda
(Ritzer, 2003).
Setelah perang dunia II, negara utama yang terlibat
yaitu eropa barat, dari dampak perang ini terjadilah kesulitan
dalam ekonomi sebagai akibat tingginya biaya perang. Untuk
memulihkan kembali kondisi akibat perang maka negara-
47
negara berupa Barat dan Amerika Serikat melakukan
konsolidasi. Hasil konsolidasi itu adalah adanya perubahan
hubungan antar negara dalam bidang sosial, ekonomi dan
politik. Dominasi kapitalisme tidak lagi diwujudkan dalam
penjajahan fisik, tetapi diwujudkan dalam penjajahan non
fisik. Sebagai contoh dibidang ekonomi dibentuknya
lembaga-lembaga ekonomi yang pada hakikatnya akan
mengendalikan negara-negara yang baru merdeka, seperti
lembaga ekonomi berikut: World Bank yang dibentuk pada
tahun 1946, international monetary find (IMF) dibentuk pada
tahun 1947, general agreement tariff and trade (GATT)
dibentuk pada tahun 1947 (Samekto, 2005).
Hypermarket Sebagai Pusat Kebudayaan (contoh kasus)
Sebagai sebuah pasar, hypermarket tidak lagi sekedar
berfungsi sebagai arena transaksi, tetapi juga sebagai tempat
akulturasi, tempat belajar, tempat berguru, tempat mencari nilai-
nilai, tempat membangun citra diri, tempat merumuskan
eksistensi diri, tempat mencari makna kehidupan, tempat
pertapaan, (mencari ketenangan, menghilangkan stress), tempat
terapi jiwa (mencari kesenangan, kegairahan, kegembiraan),
serta tempat upacara ritual abad ke-21 -fashion show, opening
ceremony, louching ceremony) (Piliang, 2009). Lewat jutaan
tanda dan citra-citra yan dikonstruksi dan disuguhkannya,
hypermarket menjadi sebuah arena pertarungan dan sekaligus
kontradiksi tanda-tanda. Ia menciptakan masyarakat consumer
sebagai petarung-petarung semiotika.
Ia menjadi sebuah arena pengetesan tanda dan kode-
kode social (Piliang, 2009). Yang dirayakan di dalam
hypermarket adalah permainan bebas tanda-tanda. Pilihan
anda adalah sebuah consensus, sebuah verifikasi terhadap
kebenaran kode-kode yang telah dirumuskan oleh anda.
Hypermarket adalah bentuk sosialisasi masa depan yang
dikendalikan dari atas oleh para elit, yang di dalamnya
dikonstruksi durasi ruang dan waktu, tempat lalu lintas tidak
saja barang dan jasa, tetapi juga tubuh, hasrat dan libido,
48
tempat lalulintas kehidupan social (kerja, waktu senggang,
makanan, kesehatan, transportasi, hiburan, media,
kebudayaan), tempat bertemunya segala kontradiksi social,
ruang waktu bagi beroperasinya segala bentuk simulacrum
kehidupan social, tempat bertemunya segala struktur dan lalu
lintas kehidupan (Piliang, 2009).
Hypermarket tidak saja sebagai jalur lalu lintas barang
dan jasa, akan tetapi juga lalulintas gaya, gaya hidup, identitas,
nilai-nilai, yang berganti dan berpindah-pindah tanpa hentinya,
layaknya nomad. Hypermarket dalam hal ini, menjadi sebuah
arena pertukaran hasrat (Piliang, 2009). Di dalamnya orang
membeli kebenaran (moral, spiritual, social, kultural) dengan
harga yang murah, sementara membeli kesemuan, kepalsuan,
ilusi, halusinasi, dan ekstrimitas dengan harga yang mahal
(ekstasi, citraan, kemewahan, prestise.
Menelanjangi Konsumerisme
Arus konsumerisme yang melanda negara-negara
berkembang seperti Indonesia mengkondisikan masyarakatnya
untuk hidup boros. Oleh karena itu, saatnya mengobarkan
perang melawan konsumerisme. Perang di sini diartikan
dengan sikap kritis praktik konsumtif selama ini, komitmen
untuk tidak hidup boros, melakukan skala prioritas kebutuhan,
tidak hanyut oleh iming-iming iklan, dan meningkatkan
produktivitas sendiri.
Jangan biarkan, bangsa ini seperti yang digambarkan
sastrawan Pramoedya Ananta Toer, sebagai negara kaya tapi
suka mengemis. Sudah mengemis, hidup boros lagi. Suatu
yang ironis. Para kapitalis sangat bergangtung pada konsumen
untuk menjaga operasi ekonomi pada tingkat pertumbuhan
yang tinngi, kapitalis adalah kekuatan utama bagi penemuan
alat konsumsi baru yang ada, seperti kartu kredit, shopping
mall, jaringan tv shopping, katalog-katalog. Dikatakan bahwa
jika masyarakat postmodern adalah masyarakat konsumsi,
maka alat konsumsi baru tersebut adalah elemen kunci dunia
postmodern (Ritzer, 2003:374).
49
Jane Baudrillard (dalam Foster, 1988: 46) kegiatan
konsumsi adalah kegiatan komunikasi. Yang mana ketika kita
mengonsumsi sesuatau berarti kita mengkomunikasikan pada
orang lewat perbedaan tanda/ objek. Orang tau kenapa kita
lebih memilih beli BMW dari pada Hyundai. Kita tidak
membeli apa yang kita butuhkan tetapi membeli apa yang
kode sampaikan kepada kita tentang apa yang seharusnya
dibeli (Ritzer, 2003). Konsumerisme adalah suatu pola pikir
serta tindakan dimana orang melakukan tindakan membeli
barang bukan dikarenakan ia membutuhkan barang itu tetapi
dikarenakan tindakan membeli itu sendiri memberikan
kepuasan bagi dirinya. Fenomena yang menonjol dalam
masyarakat Indonesia saat ini, yang menyertai kemajuan
ekonomi adalah berkembangnya budaya konsumsi yang
ditandai dengan berkembangnya gaya hidup.
Berbagai gaya hidup yang terlahir dari kegiatan
konsumsi semakin beragam pada masyarakat perkotaan
Indonesia. Kalau dulu ada istilah yang populer dari Descartes,
yakni “Cogito ergo Sum: Aku berpikir maka aku ada”, tetapi
sekarang istilah yang populer (Adikila, 2013), adalah: ”I shop
therefore I am: Aku berbelanja maka aku ada”.
50
“Money Politic” Menjadi Agama Baru
(Telaah Sosiologis Fenomena Pemilihan Presiden 2014)
M. Chairul Basrun Umanailo & Tri Yatno
Pada 9 Juli 2014 nanti kita akan menemukan sebuah
ritual pemilihan Presiden, ritual yang bagi kebanyakan orang
merupakan hal penting untuk memilih siapa yang akan
memimpin negara dan rakyat Indonesia untuk lima tahun
kedepan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengambarkan
sebuah kondisi yang hampir dipastikan akan muncul disetiap
pesta pemilihan presiden yaitu “Money Politic”. Bagi saya,
money politik merupakan sebuah perilaku yang sudah hampir
melembaga, bahkan sebentar lagi akan menjadi agama baru
51
bagi politikus yang ingin sesuatunya instan, dan itu bagi saya
bukanlah suatu kesalahan (relatif).
Bicara tentang money politik selayaknya kita bicara
hukum, dan hukum itu tidak sekedar intepretasi atas pasal
dan ayat namun lebih jauh bicara tentang keadilan yang akan
lahir dari hukum yang dikonstruksi dan melahirkan sebuah
keadilan yang sering kita pertanyakan apakah keadilan
subtansif ataukah keadilan formal yang kita pahami sebagai
keadilan procedural dari hukum yang dibuat.
Mengapa kemudian money politik bisa terjadi, kalau
ditinjau secara Sosiologis, masyarakat kita telah menyerupai
masyarakat konsumsif, masyarakat yang bagi Baudrillard
lebih mementingkan konsumsi ketimbang produksi, yang
pada akhirnya menimbulkan perilaku hedonism dalam
kesehariannya. Konsekuensi social yang bisa kita dapatkan
yaitu bergesernya nilai Keindonesiaan yang kental dengan
kekerabatan dan gotong royong menjadi individualistic yang
mencitrakan sebagai individu yang sangat rasional. Padahal
dibalik itu masyarakat kitamasih sangat rapuh untuk
kohesivitas social, akibat uang 50.000 seorang kakak bisa
melupakan adiknya, seorang guru menyangkal muridnya
hanya karena berbeda tawaran politik.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian money
politik itu bisa kita anggap salah? Bagi penganut keadilan
subtansif akan berpendapat “belum tentu” tetapi bagi mereka
yang men-Tuhan-kan proses hukum akan mengatakan Iya.
Hukum tentunya memiliki dimensi keadilan, dimensi yang
mana setiap pengikutnya akan merasa nyaman dan
terlindungi dalam dimensi tersebut.
Ada dua keadilan yang bisa kita kaitkan dengan
fenomena money politik, pertama, bahwasanya keadilan
tidak bisa mentolerir sebuah perbedaan dengan individu,
bagipenganut Durkheimian hal ini akan dianggap sebagai
patologi, berbeda ketika masalah ini kitaperhadapkan dengan
penganut Weberian, yang serta merta akan menganggap
52
sebuah kebenaranakan dikonstruksi oleh individu dengan
rasionalitasnya.
Bagi Sosiolog, keadilan ibarat pedang bermata dua.
Saya sempat membaca tulisan Yusril Izha Mahendra pada
beberapa waktu yang lalu, Ketika negara tidak berfungsi
mengatasi kemiskinan, Abang Jampang atau Robinson
Crusoe merampok dimana-mana yang hasil rampokannya
dibagikan kepada orang miskin. Dari sudut keadilan
substantif, mungkin apa yang dilakukan Jampang dan
Robinson mungkin benar. Tapi dari sudut prosedural yang
dilakukannya terang salah. Dari keadilan substantif pun
merampok tetap salah, hanya karena ada alasan pembenar
saja, maka tindakan itu secara substantif terlihat adil,
sehingga secara prosedural, tindakan keduanya dapat
"dimaklumi". Maka ketika ilustrasi inisaya kaitkan dengan
money politik akan tergambar bahwasanya secara subtansif
sang pemberi uang akan terlihat seperti si Jampang namun
ketika berhadapan dengan procedural maka Jampang akan
disalahkan dengan struktur dan prosedur hukum yang
berlaku. Inilah gambaranPosmoralitas, yang dikutip sebagai
sebuah situasi bercampuraduknya tindakan moral
dantindakan amoral, dan melahirkan dilematis pada dimensi
keadilan.
Dalam anatomi Sosiologi, nilai merupakan derajat
tertinggi yang merupakankonstruksi dari berbagai norma, dan
ketika norma menjadi uraian tanda (sign) maka nilai
tersebutakan menjadi sebuah pembenaran yang hakiki.
Money politik terbangun dengan tanda kepercayaan dan
kepentingan, bahwasanya seseorang akan melakukan money
politik sebagai penanda kepercayaan pada orang lain untuk
memilihnya sementara petanda sebagai wujud kepentingan
praktis untuk mendapatkan kekuasaan.
Bila kondisi ini dipertahankan dan menjadi kebiasaan
yang terus menerus serta terlembaga maka money politik
akan terkonstruksi menjadi Fakta Sosial yang memiliki sifat
memaksa dan eksternal, Pada akhirnya, ketika money politik
53
sudah terlembaga dan menjadi tanda maka dalam kehidupan
berpolitik di Indonesia akan lahir agama baru yang namanya
“Money Politik”.
Bahkan saat pelaku politik tidak melakukan money
politik bisa dianggap dosa besar karena menyalahi dogma
agama yang dianutnya. Sekarang tinggal bagaimana
masyarakat memutuskan untuk murtad dan memilih agama
money politik sebagai agama barunya, atau tetap bertahan
dengan agama lama yang mengajarkan nilai-nilai
kepercayaan, bahwa sesuatu kesuksesan tidak datang dengan
paksaan akan tetapi terjewantahkan dengan doa dan kerja
keras.
Namun dibalik semua itu masyarakat kita secara
subjektif masih berupa “masyarakat kepentingan” takut
beragama politik ketika belum memiliki kepentingan dan
akan menjadi pemeluk yang setia membela agama, saat
kepentinganya terakomodir dalam salah satu agama politik.
Semoga Tuhan tidak keliru.
54
PIDATO DAN PENGHANCURAN
LABEL CALON PRESIDEN 2014
M. Chairul Basrun Umanailo
Selasa malam, tepatnya 3 Juni 2014 merupakan puncak
deklarasi bagi calon Presiden, Prabowo dan Jokowi harus
maju ke depan untuk menyampaikan pidato tentang
komitmen mereka untuk menjalankan proses pemilihan
presiden dengan damai. Apa makna dibalik pidato yang
disampaikan oleh mereka berdua, adakah yang kemudian
mampu memaknai makna dibalik apa yang disampaikan oleh
55
mereka, atau kita hanya sekedar beranggapan bahwa yang
penting bukti kerja bukan pidatonya.
Pidato bagi sebagian orang merupakan gambaran
intelektual, gambaran bagaimana seseorang mengemukakan
ide atau gagasan yang dapat dimaknai secara simbolik, tesis
Ernst Cassirer bahwa manusia adalah mahluk simbolik yang
dalam kesehariannya dari bangun tidur hingga tidur kembali
merupakan rangkaian simbolik yang saling memiliki
hubungan. Sementara itu, Pidato merupakan rangkaian
pemikiran untuk melahirkan sebuah gagasan dengan
menggunakan media bahasa.
Disinilah mulai ditafsirkan pidato sebagai media
pencitraan dengan permainan bahasa-bahasa yang
memikatbahkan mampu menjungkir balikan realitas yang
sebenarnya. Selain itu permainan bahasa sebagai simbol juga
mampu menjadi konstruksi realitas bagi seseorang, terlebih
bagi Prabowo maupun Jokowi disaat gencarnya kampanye
hitam yang telah lebih dulu mencuri start kampanye.
Prabowo yang diberikan kesempatan pertama untuk
berpidato, mencoba untuk menghancurkan nilai-nilai yang
dianggap otoriter kepadanya dengan begitu menyerahkan
sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat. Prabowo mencoba
menghapus arogansi yang selama ini dilabelkan padanya
dengan bersusah payah menyusun kalimat persaudaraan dan
patriotisme. Cukup mencengangkan dengan kalimat “kita
serahkan” jelas bahwa Prabowo mencoba mengkonstruksi
nilai-nilai kerelaan dalam sebuah proses demokrasi. Timbul
pertanyaan yang menarik, mengapa kemudian Prabowo harus
menghancurkan pelabelan arogansi terhadap dirinya, padahal
ia sendiri dikonstruksi dengan pendidikan militer yang
notabene sangat memungkinkan untuk melembaga arogansi
dalam pribadinya, dan Prabowo hanya sekedar meyakinkan
pada publik bahwa ikon ketegasan yang dimilikinya tidak
linear dengan arogansi yang dituduhkan selama ini.
Kemudian Jokowi yang memulai dengan sebuah salam
dan shalawat yang cukup mencengangkan, melahirkan
56
aggapan baru bahwa saya muslim yang sejati, toh derajat
keislaman tidak harus diukur dengan salam yang menyerupai
tablig akbar. dengan keinginan untuk menghancurkan
pelabelan muslim yang belum sholeh Jokowi berusaha
mengkonstruksi semua itu bahwa cukup anda tahu bahwa
saya fasih untuk membaca Alquran, karena tuduhan dengan
status Keislamannya maka diciptakan ikon dalam berpidato
yang mampu menghancurkan semua pelabelan tersebut.
Pada suatu kesimpulan, Prabowo dan Jokowi sama-
sama menciptakan ikon sebagai simbol perlawanan terhadap
tuduhan bahkan pelabelan yang diarahkan kepada mereka
berdua. Prabowo berulang kali merendah, mencoba
melahirkan penafsiran yang berbeda dari sebelumnya, juga
Jokowi dengan ikon salam berusahan mematahkan lebel yang
dianggap mampu ditepis walau dalam sebuah medan
pertarungan simbol dalam berpidato.
Pertanyaan selanjutnya, ini sebuah euphoria demokrasi
ataukah konstruksi identitas lewat bahasa dalam pidato?
Seandainya sebuah euphoria haruslah lebih mencitrakan
sebuah kegembiraan, optimism dan meleburnya semua
ketegangan, namun bagi saya pribadi, pidato yang terjadi
lebih merupakan upaya dekonstruksi atas citra yang
diberikan kepada mereka atau meminjam konsep Budrillard,
pidato sebagai simulasi.
Pidato yang disampaikan mengantarkan kita pada
sebuah dunia representasi yang di dalamnya sebuah bentuk
atau simbol berfungsi seakan-akan sebagai presentasi dri
sebuah realitas yang menjadi rujukannya. Ada ketakutan
yang lahir apabila kemudian isi dari pidato lebih berupa
simulacrum, dengan duplikasi ikon, duplikasi harapan namun
sebaliknya semua itu hanya permainan bahasa untuk
mencapaitujuan yang masih tersembunyi.
Apa yang ditakutkan Prabowo dengan label arogansi,
dan apa pula yang dikhawatirkan Jokowi dengan keislaman.
Apakah kemudian seorang presiden harus memiliki sikap
yang manut, tunduk dan harus selalu sabar? Atau seorang
57
Presiden dengan status keislaman yang bertaraf santri, yaitu
bisa menghafal Alquran dan taat dalam beribadah? Itu semua
hanya fakta social, situasi yang memaksa individu untuk
menyesuaikan dengan keinginannya.
Harapannya bahwa pidato mereka berdua lebih
merupakan suatu proper sign dapat kita kaji lewat tulisan
Yasraf Amir Piliang (Posrealitas) yaitu tanda yang
merupakan cermin realitas; ia menyatakan makna yang
sebenarnya; membentangkan kebenaran; menyikap keaslian;
menjadi refleksi dari realitas. Ia adalah tanda yang jujur, asli,
tulen dan apa adanya, yang oleh Baudrillard dikategorikan
sebagai ordepetanda, yaitu tanda yang merefleksikan realitas.
Semoga yang disampaikan adalah konstruksi realitas yang
akan dibangun bukan sebaliknya sebuah penopengan realitas
lewat tanda.
58
POSTMODERNISME DALAM PANDANGAN JEAN FRANCOIS LYOTARD
M. Chairul Basrun Umanailo
“Postmodernisme” adalah istilah yang sangat
kontroversial. Di satu pihak istilah ini telah memikat minat
masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki
kemampuan untuk mengartikulasikan beberapa krisis dan
perubahan sosio-kultural mendasar yang kini sedang kita
alami. Di lain pihak istilah ini dianggap sebagai mode
intelektual yang dangkal dan kosong atau sekedar refleksi
yang bersifat reaksioner belaka atas perubahan sosial yang
kini sedang berlangsung.
59
Jean Francois Lyotard adalah seorang filosof
poststrukturalisme namun ia kemudian lebih dikenal sebagai
salah satu pemikir penting aliran filsafat postmodernisme
yang terkenal dengan gagasannya tentang penolakan Grand
Narrative (narasi besar), yaitu suatu cerita besar yang
mempunyai fungsi legitimasi karena bersifat menyatukan,
universal, dan total. Penolakan narasi besar, menurut
Lyotard, berarti penolakan terhadap penyatuan, universalitas
dan totalitas. Dan dalam pandangannya, inilah salah satu ciri
pembeda yang paling menonjol antara filsafat
postmodernisme dengan filsafat modernisme.
Istilah “postmodernisme” muncul pertama kali di
kalangan seniman dan kritikus di New York pada 1960-an
dan diambil alih oleh para teoretikus Eropa pada 1970-an.
Salah satunya, Jean-François Lyotard, dalam bukunya, The
Postmodern Condition: A Report on Knowledge, menyerang
mitos yang melegitimasi jaman modern (“narasi besar”),
pembebasan progresif humanitas melalui ilmu, dan gagasan
bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan untuk proses
memahami dan mengembangkan pengetahuan yang secara
universal sahih untuk seluruh umat manusia. Lyotard percaya
bahwa kita tidak dapat lagi bicara tentang gagasan penalaran
yang mentotalisasi karena penalaran itu tidak ada, yang ada
adalah pelbagai macam penalaran. Lyotard melihat bahwa
filsafat sebagai pemaksaan kebenaran. Ia melawan Marxisme
karena Marxisme dipandang sebagai salah satu “narasi
besar”. Lalu Lyotard menyarankan untuk kembali ke
“pragmatika bahasa” ala Wittgenstein, yaitu mengakui saja
bahwa kita memang hidup dalam pelbagai permainan-bahasa
yang sulit saling berkomunikasi secara adil dan bebas.
Lyotard melihat masyarakat kita saat ini adalah
masyarakat yang individualistik, terfragmentasi. Ia
merindukan masyarakat pramodern yang sangat menekankan
nilai penting narasi, yakni mitos, kekuatan gaib,
kebijaksanaan rakyat, dan bentuk-bentuk penjelasan lain. Dia
percaya bahwa terjadi konflik antara narasi dan ilmu. Narasi
60
menghilang dan tidak ada yang bisa menggantikannya.
Pendek kata, Lyotard berpendapat bahwa narasi besar itu
buruk, narasi kecil itu baik. Narasi akan menjadi buruk bila
berubah menjadi filsafat sejarah. Narasi besar diasosiasikan
dengan program politik atau partai, sementara narasi kecil
diasosiasikan dengan kreativitas lokal.
Jean Francois Lyotard dalam pemikiran filosofisnya
banyak dipengaruhi oleh Karl Marx, Nietzsche, Immanuel
Kant, Sigmund Freud. Pengaruh Karl Marx nampak sekali
dari pandangannya yang tidak menyukai kesadaran universal.
Sedangkan Nietzsche mempengaruhi pemikiran Lyotard
dalam hal bahwa tidak ada perspektif yang dominan dalam
ilmu pengetahuan. Tidak ada teori yang obyektif universal.
Sementara itu yang diambil dari Immanuel Kant adalah
konsep Kant yang membedakan antara domain teoritis
(ilmiah), praktis (etis), dan estetis dimana masing-masing
memiliki otonomi, aturan dan kriteria sendiri. Pengaruh
Sigmund Freud berada dibalik pemahaman Lyotard tentang
politik hasrat.
Riwayat Hidup Jean Francois Lyotard lahir di Versailles, Perancis
pada tahun 1924 dan meninggal dunia di Paris pada tahun
1998. Setelah lulus dari Universitas Sorbonne pada tahun
1950, Lyotard menjadi guru SMU di Constantine, Aljazair. Ia
kemudian bersimpati dan terlibat dengan gerakan
kemerdekaan Aljazair dan akhirnya kembali ke Paris pada
tahun 1959 untuk menjadi asisten dosen di almamaternya,
Universitas Sorbonne. Pada tahun 1960-an ia mengajar di
Naterre, tetapi senantiasa bersama kaum terpelajar lainnya
seperti Sartre, Deleuze, Foucault, Lacan terlibat dan aktif
dalam gerakan anti perang. Tahun 1970 – 1972, ia mengajar
di Institute Polytechnique de Philosophie Vincennes, dan
dilanjutkan di Universaitaire de Paris VIII St. Denis pada
tahun 1972 – 1987.
61
Lyotard meraih gelar doktor sastra pada tahun 1971
dengan desertasi yang berjudul, Discours, figure yang
membahas tentang problematika bahasa dengan
membandingkan antara pendekatan strukturalisme dan
fenomenologi. Dengan cara ini, ia berharap dapat melampaui
aliran strukturalisme dan memposisikannya sebagai salah
seorang tokoh poststrukturalisme dan postmodernisme
Perancis terkemuka.
Sepanjang karir akademiknya, Lyotard telah
menghasilkan beberapa karya penting yang mendongkrak
popularitasnya di dunia akademik terutama dalam bidang
filsafat. Beberapa karyanya tersebut adalah :
1. La Phenomenologie (1954)
2. Discours, Figure (1971)
3. De`rive a`partire de Marx et Freud (1973)
4. Libidinal Economy (1973)
5. La Condition Postmoderne, Rapport sur le Savoir (1979)
6. Just Gaming (1979)
7. The Different : Phrases ini Dispute (1983)
8. The Inhuman : Reflections on Time (1988)
9. The Lyotard Reader (1989)
10. The Postmodern Explained to Children
Pemikiran-pemikirannya
Runtuhnya Narasi Besar (Grand Narratives) Meskipun pada tahun 1950 dan 1960-an ia adalah
aktivis politik dengan pandangan-pandangan Marxis, pada
tahun 1980-an Lyotard menjadi seorang filosof
postmodernisme non-Marxis. Oleh sebab itu,
postmodernisme menjadi sebuah keterlepasan mendasar dari
pemikiran totaliter yang diwakili oleh Marxisme. Sebelum
terbitnya buku yang merupakan karyanya yang terpenting
dalam bidang filsafat berjudul The Differend: Phrases in
Dispute, Lyotard sudah menunjukkan arah perubahan
filosofis ini. Tahun 1954 terbit buku pertama Lyotard yang
berjudul La Phenomenologie yang merupakan buku
62
pengantar dalam memahami fenomenologi Husserl.
Meskipun ia pengikut kelompok Marxis akan tetapi ia selalu
kritis dan menolak interpretasi dogmatis terhadap pemikiran
Marx seperti yang dilakukan Stalinisme, Trotskyisme, dan
Maoisme.
Dua belas tahun kemudian setelah terbit buku
pertamanya tersebut yakni tahun 1966, ia resmi menyatakan
keluar dari Marxis karena ia merasa kecewa dengan
kegagalan gerakan Marxis untuk membangun masyarakat
sosialis yang adil sebagaimana digembar-gemborkan selama
ini. Sebaliknya, Marxisme berusaha menciptakan masyarakat
yang homogen yang hanya dapat diwujudkan dengan cara
kekerasan dan pelanggaran hak-hak azasi manusia. Lyotard
sangat tidak setuju dengan keseragaman atau upaya
menyeragamkan apalagi upaya tersebut dicapai dengan jalan
kekerasan. Baginya, salah satu karakteristik masyarakat
postmodern adalah indivualis dan kebebasan untuk berbeda
dengan yang lain.
Istilah postmodern itu sendiri sebagai kritik terhadap
filsafat modern ia perkenalkan pertama kali di dalam
bukunya yang terkenal “La Condition Postmoderne, Rapport
sur le Savoir” terbit tahun 1979 dan diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dengan judul “The Postmodern Condition: A
Report on Knowledge.”Edisi bahasa Inggrisnya terbit pada
tahun 1984 dan sejak itu ia menjadi locus classicus untuk
diskusi-diskusi tentang postmodernisme di bidang filsafat.
Buku ini sebetulnya merupakan sebuah laporan yang diminta
oleh dewan ahli Universitas Quebec tentang masyarakat yang
telah mencapai kemajuan dalam bidang pengetahuan dan
teknologi akhir abad ke-20. Ia diminta untuk menjelaskan
dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi
informasi terhadap ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-20
tersebut. Dalam buku itu, ia mengatakan bahwa telah terjadi
perkembangan dan perubahan yang luar biasa pada
pengetahuan, sains dan pendidikan pada masyarakat
informasi.
63
Perkembangan dan perubahan tersebut telah
menggiring masyarakat tersebut pada suatu kondisi yang dia
sebut sebagai postmodern. Selama empat puluh tahun
terakhir ilmu dan teknologi yang terdepan menjadi semakin
terkait erat dengan bahasa, teori-teori linguistik, masalah
komunikasi dan sibernetik, komputer dan bahasanya,
persoalan penerjemahan, penyimpanan informasi, dan bank
data. Transformasi teknologi berpengaruh besar pada
pengetahuan. Miniaturisasi dan komersialisasi mesin telah
merubah cara memperoleh, klasifikasi, penciptaan, dan
ekspoitasi pengetahuan. Dan Lyotard percaya bahwa sifat
pengetahuan tidak mungkin tidak berubah di tengah konteks
transformasi besar ini. Status pengetahuan akan berubah
ketika masyarakat mulai memasuki apa yang disebut zaman
postmodern. Pada tahap lebih lanjut, pengetahuan tidak lagi
menjadi tujuan dalam dirinya sendiri namun pengetahuan
hanya ada dan hanya akan diciptakan untuk dijual.
Dalam buku tersebut, pemikiran Lyotard umumnya
berkisar tentang posisi pengetahuan di abad teknologi
informasi ini, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasikan
melalui, yang disebutnya, “narasi besar” (grand narrative),
seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar dan
sebagainya. Menurut Lyotard, narasi-narasi besar ini telah
mengalami nasib yang sama dengan narasi-narasi besar
sebelumnya seperti religi, negara-kebangsaan, kepercayaan
tentang keunggulan Barat dan sebagainya, yaitu mereka pun
kini menjadi sulit untuk dipercaya. Dengan kata lain, dalam
abad ilmiah ini narasi-narasi besar menjadi tidak mungkin,
khususnya narasi tentang peranan dan kesahihan ilmu itu
sendiri. Dalam kerangka ini pula, aspek mendasar yang
dikemukakan oleh Lyotard pada dasarnya merupakan upaya
tentang kemustahilannnya membangun sebuah wacana
universal nalar sebagaimana diyakini oleh kaum modernis.
Bagi Lyotard dengan postmodernisme-nya
menganggap bahwa untuk mengaktifkan ilmu pengetahuan
adalah dengan menghidupkan perbedaan-perbedaan,
64
keputusan-keputusan, dan keterbukaan pada tafsiran-tafsiran
baru. Ia tidak percaya bahwa ilmu pengetahuan dapat
diwadahi oleh suatu badan pemersatu yang berupa sistem
stabil. Sebab menurutnya, ilmu pengetahuan itu tumbuh
sebagai sistem yang organik, dalam arti tidak homogen
apalagi tertutup pada eksperimentasi dan permainan berbagai
kemungkinan wacana. Dari perspektif Lyotard ini, secara
jelas kita dapat memahami bahwa postmodernisme adalah
usaha penolakan dan bentuk ketidakpercayaan terhadap
segala “Narasi Besar” filsafat modern; penolakan filsafat
metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk pemikiran yang
mentotalisasi –seperti Hegelianisme, Liberalisme, Marxisme,
atau apapun. Secara demikian, Postmodernisme, sambil
menolak pemikiran yang totaliter, juga mengimplikasikan
dan menganjurkan kepekaan kita terhadap perbedaan dan
memperkuat toleransi terhadap kenyataan yang tak terukur.
Postmodernisme dengan demikian lahir untuk menolak
anggapan-anggapan modernisme yang membawa keyakinan
bahwa filsafat melalui rasio sebagai sarananya mampu
merumuskan hal-hal yang dapat berlaku secara universal.
Postmodernisme menolak cara pandang tunggal atau
paradigma tunggal dan sebaliknya menyatakan bahwa
terdapat banyak paradigma atau perspektif dalam melihat
realitas dunia. Pandangan ilmu yang obyektif universal harus
digantikan oleh hermeneutika tentang realitas.
Menurut Webster sebagaimana dikutip oleh Akhyar
Yusuf dalam laporan penelitiannya mengatakan bahwa ada
beberapa elemen kunci pemikiran postmodern sebagai suatu
gerakan intelektual dan sebagai fenomena sosial yang
membedakannya dengan modern, diantaranya adalah
1. Penolakan terhadap pemikiran modernis, nilai-nilai dan
praktek-prakteknya.
2. Penolakan terhadap klaim-klaim penelitian tentang klaim
“kebenaran obyektif universal” dan penolakan terhadap
fundasi epistemologinya (antifundasionalisme), lalu yang
ada dan diterima hanya versi-versi dari “kebenaran”.
65
3. Penolakan tentang autentisitas dari penelitian, karena
semuanya dianggap tidak otentik, semuanya lebih
bersifat konstruktif.
4. Penolakan terhadap masalah/pertanyaan tentang
identifikasi makna karena ada suatu ketidakterbatasan
makna (infinity of meaning).
5. Penghargaan pada perbedaan: interpretasi, nilai-nilai, dan
gaya (the celebration of diffferences, of interpretations,
of values, and of style).
6. Suatu penekanan pada kenikmatan, pada pengalaman
sebagai hal utama untuk dianalisa, pada juoissance and
the sublime (luhur).
7. Suatu kesukaan (delight) pada superficial, penampakan,
perbedaan, parodi, ironi, dan pastis (pastiche).
8. Pengakuan/penghargaan pada kreativitas dan imajinasi
daripada keteraturan dengan defies (muslihat) penjelasan
determinisme tingkah-laku.
Memudarnya kepercayaaan kepada narasi besar
disebabkan oleh proses delegitimasi atau krisis legitimasi,
dimana fungsi legitimasi narasi-narasi besar mendapatkan
tantangan-tantangan berat. Sebagai contoh, delegitimasi
adalah apa yang dialami ilmu sejak akhir abad ke-19 sebagai
akibat perkembangan teknologi dan ekspansi kapitalisme.
Dalam masyarakat pasca industri, ilmu mengalami
delegitimasi karena terbukti tidak bisa mempertahankan
dirinya terhadap legitimasi yang diajukannya sendiri.
Legitimasi ilmu pada narasi spekulasi yang mengatakan
bahwa pengetahuan harus dihasilkan demi pengetahuan di
masa capitalist techno science tidak bisa lagi dipenuhi.
Pengetahuan tidak lagi dihasilkan demi pengetahuan
melainkan demi profit dimana kriteria yang berlaku bukan
lagi benar-salah, melainkan kriteria performatif yaitu,
menghasilkan semaksimal mungkin dengan biaya sekecil
mungkin.
66
Pengetahuan Narasi dan Pengetahuan Ilmiah Pengetahuan ilmiah tidak merepresentasikan totalitas
pengetahuan karena pengetahuan ilmiah selalu bersaing
dengan pengetahuan lain, atau menurut Lyotard disebut
sebagai narasi. Pada masyarakat tradisional, narasi seperti ini
menjadi penting. Narasi menentukan kriteria kompetensi
serta menjelaskan bagaimana kriteria tersebut diterapkan.
Perbedaan utama pengetahuan ilmiah dan pengetahuan
narasi adalah bahwa pengetahuan ilmiah mengandaikan
hanya ada satu permainan bahasa, yakni bahasa denotatif,
sementara permainan bahasa yang lain harus diabaikan.
Sedangkan pengetahuan narasi mengesahkan diri tanpa harus
merujuk pada argumen dan bukti atau tanpa harus
menggunakan verifikasi dan falsifikasi. Karena itu, para
ilmuwan mempersoalkan validitas kebenaran pernyataan-
pernyataan narasi dan menyimpulkan bahwa pengetahuan
narasi itu tidak tunduk pada argumen dan bukti. Baik
pengetahuan ilmiah dan pengetahuan narasi adalah sama-
sama penting. Keduanya tersusun dari serangkaian
pernyataan yang dilontarkan oleh para pemain dalam
kerangka peraturan yang dapat diterapkan secara umum.
Peraturan-peraturan itu bersifat khusus pada setiap jenis
pengetahuan. Pernyataan yang dianggap baik dalam suatu
jenis pengetahuan tertentu pasti akan berbeda dengan
pernyataan yang dipandang baik dalam jenis pengetahuan
yang lain. Oleh sebab itulah, maka tidak mungkin menilai
eksistensi dan validitas pengetahuan non ilmiah atau narasi
berdasarkan pengetahuan ilmiah ataupun sebaliknya karena
kriteria atau permainan bahasa yang digunakan tidak sama.
Perbedaan bahasa yang dimaksud adalah perbedaan
kultur bukan sebagai pembedaan yang satu lebih baik dari
yang lain karena ilmu tidak menerima sudut pandang. Jika
ilmu menggunakan bahasa denotatif dan pembenarannya
dilakukan melalui verifikasi fakta internal, maka pengetahuan
narasi menggunakan bahasa metafor.
67
Permainan Bahasa Sejak beberapa dekade yang lalu beredar istilah
“Linguistic Turn”. Meskipun istilah ini kini memang telah
memudar, tapi esensinya masih berbunyi: bahasa adalah tema
sentral filsafat abad 20. Kini banyak tema pokok tradisional
filsafat memang berlabuh dalam persoalan bahasa. Tentu saja
sejak zaman Yunani, bahasa sudah selalu berperan penting
dalam filsafat. Namun, selama itu, bahasa itu sendiri tidak
pernah sungguh-sungguh dipersoalkan sebagai tema utama.
Baru pada awal abad 20, sejak G. E. Moore dan Bertrand
Russell yang memuncak pada Wittgenstein, bahasa menjadi
tema kajian utama, bahkan hingga kini (abad 21). Tradisi
analitik ini mencoba menunjukkan bahwa banyak persoalan
dasar filsafat tradisional hanyalah semu: hanya perkara logika
dan bahasa belaka. Sejak itu, mulai ada kecenderungan kuat
untuk memperkarakan hakekat “filsafat” itu sendiri dari
sudut bahasa. Dengan kata lain, terjadi kesibukan menuju ke
arah filsafat tentang filsafat: “Metafilsafat”.
Perspektif yang terakhir itu memunculkan issue baru
seperti: apakah bahasa pengetahuan itu memang harus satu
dan universal, katakanlah bahasa “ideal” seperti yang umum
dicita-citakan filsafat modern, ataukah dibiarkan saja dalam
berbagai “Language games” sesuai dengan bentuk-bentuk
kehidupan yang memang beragam, sebutlah bahasa “natural”.
Kebenaran dan penalaran dilihat erat berkaitan dengan
bahasa.
Dalam zaman kontemporer dimana kerumitan
dianggap semakin meningkat maka semakin jauhlah
kemungkinan adanya penjelasan tunggal atau ganda tentang
pengetahuan atau ilmu. Sebelumnya, keyakinan terhadap
suatu narasi (misalnya, doktrin-doktrin agama) bisa
memecahkan kesulitan ini. Sejak perang dunia ke-2, seperti
yang sudah diantisipasi oleh Weber, teknik dan teknologi
telah “mengalami pergeseran penekanan dari tujuan tindakan
ke caranya. Dengan menafikan baik itu bentuk unifikasi
naratif sebagai yang bersifat spekulatif maupun yang
68
berbentuk emansipatoris, legitimasi terhadap pengetahuan
tidak bisa bersandar pada satu narasi besar sehingga ilmu itu
sekarang paling baik dipahami dalam pengertian teori
“permainan bahasa” menurut Wittgenstein. Permainan
bahasa menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep atau
penjelasan ilmiah atau teori yang dapat menangkap realitas
dalam totalitasnya secara memadai. Oleh karena itu,
permainan bahasa tidak dapat diharapkan untuk dapat
menjelaskan realitas apa adanya karena ia adalah salah satu
permainan diantara keragaman permainan bahasa lainnya.
Lyotard meyakini bahwa tidak ada kesatuan dan inti
sari bahasa. Baginya bahasa adalah “agonistic” yakni suatu
ruang atau tempat perselisihan dan konflik yang tidak pernah
bisa diselesaikan. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak dapat
dibandingkan. Tidak ada permainan lain, bahasa lain, dan
prase lain yang dapat mendamaikan perbedaan-perbedaan
tersebut. Ide tentang keadilan bagi Lyotard berasal dari
kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak bisa
dan seyogyianya tidak diselesaikan karena perbedaan-
perbedaan tersebut secara fundamental tidak bisa
didamaikan. Paling tidak, menurut Lyotard, ada tiga jenis
permainan bahasa yang lazim dimainkan, yaitu:
1. The denotative game
Fokus permainan bahasa ini adalah pada apa yang
benar atau salah. Ini adalah suatu permainan ilmiah
yang sederhana, dimana fakta-fakta sajalah yang
diperhitungkan. Perhatikan bahwa makna denotatif
adalah sederhana dan dengan satu makna, sedangkan
arti konotatif rumit, mendalam dan individual.
2. The prescriptive game
Fokus permainan bahasa ini adalah pada baik dan
buruk, adil dan tidak adil. Ini berarti penggunaan nilai-
nilai, yang lebih sosial daripada fakta-fakta denotatif.
69
3. The technical game
Mana fokusnya adalah pada apa yang efisien atau tidak
efisien. Ini lebih faktual, meskipun nilai dapat
dimasukkan.
Permainan bahasa ilmu adalah permainan bahasa
denotatif. Aturan main permainan bahasa denotatif adalah
sebuah pernyataan harus disertai bukti dari pihak yang
mengajukan pernyataan untuk meyakinkan pihak kedua
sebagai pihak yang wajib memberikan persetujuan atau
penolakan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak
pertama. Ilmu adalah permainan bahasa yang didalamnya
terkandung aturan-aturan normatif (misalnya, pembuat
proposisi tidak boleh membuat proposisi tanpa menyediakan
bukti yang memperkuat proposisinya, pihak kedua tidak bisa
memberikan bukti melainkan persetujuan atau
penolakannya). Ilmu dihadapkan pada kenyataan bahwa ia
tidak bisa memberlakukan aturan mainnya secara universal
hingga berhak menilai mana pengetahuan absah dan mana
yang tidak. Lyotard yakin bahwa kita memasuki fase dimana
logika tunggal yang diyakini kaum modernis sudah mati
digantikan oleh pluralitas logika atau paralogi.
Oleh sebab itu, ilmu menurut Lyotard adalah sebuah
permainan bahasa yang mengikuti aturan-aturan sebagai
berikut :
1. Yang bersifat ilmiah adalah pernyataan-pernyataan
denotative (deskriptif).
2. Pernyataan ilmiah berbeda dengan pernyataan yang
menekankan ikatan-ikatan sosial (terkait dengan asal
usul).
3. Kompetensi hanya diperlukan pada pengirim pesan
ilmiah, bukan penerimanya.
4. Pernyataan ilmiah hanya ada dalam sekumpulan
pernyataan yang diuji oleh argumen dan bukti.
5. Dalam kaitannya dengan butir 4 diatas, permainan
bahasa ilmiah memerlukan suatu pengetahuan tentang
situasi pengetahuan ilmiah yang sedang berlangsung.
70
Untuk bisa dilegitimasikan, ilmu tidak memerlukan
suatu narasi, karena aturan-aturan ilmu itu bersifat
imanen dalam permainannya.
Seni dan Estetika Dalam hal pengetahuan tentang seni, Lyotard secara
tegas dan gamblang menolak pandangan Hegel tentang
kesejarahan seni (the history of art). Baginya, seni bukanlah
barang sejarah atau the thing of the past namun sebaliknya.
Lyotard secara radikal menolak adanya makna di
setiap karya seni ketika diciptakan dan dibangun. Ia juga
menolak gagasan yang menunggangi wujud dan perwujudan
seni karena menurutnya seni memiliki kapasitas energetik.
Seni sebagaimana halnya filsafat bagi Lyotard tidak ada
kaitannya dengan permasalahan makna, identitas, dan
kebenaran. Energi seni adalah dorongan yang tidak
dikendalikan oleh nalar maupun kesadaran. Lyotard
memandang seni sebagai pencarian yang menentang
kemungkinan stabilitas melalui suatu representasi. Titik
berangkatnya adalah kondisi yang berubah, misalnya saat ini
dari modern ke postmodern.
Seni dalam ranah pemikiran filsafat Lyotard bukanlah
dilihat sebagai representasi bermakna, namun sebagai daya
yang menampakkan diri. Pemahaman seni bagi Lyotard
sangatlah unik, khususnya dalam kaitannya dengan
“keindahan” atau “yang indah”. Dalam peradaban Barat, seni
adalah bagian perjuangan untuk membebaskan dari proses
dominasi wacana yang melulu didasarkan pada kaidah-
kaidah techno-science, kaidah-kaidah yang cenderung
mencari keabsahan formulasi-formulasinya dari dirinya
sendiri. Dengan kecenderungan ini, pengetahuan menjadi
mandek atau tidak produktif.
Dalam pandangan Lyotard, postmodernisme bukanlah
semacam langgam atau cara berpikir, namun lebih mengacu
pada suatu sistem keterbukaan yang memungkinkan seni
membuka keragaman yang tidak deterministik, keragaman
71
yang terkandung dalam suatu kehidupan organik yang
memiliki kaidah dan stabilitasnya sendiri tanpa dikendalikan
oleh subyek yang berpikir.
Seni di abad informasi sekarang ini berada pada suatu
proses transformasi yang diharapkan oleh Lyotard menuju
pada rekanan-bebas (Freud). Dengan kondisi inilah,
hegemoni techno-science hanya tampak sebagai kriteria
kinerjatik saja, dan tidak cenderung dan menjadi benar-benar
hegemonik.
Lyotard menerima gagasan sublim Immanuel Kant
tentang estetika. Gagasan ini justeru memperkuat
keyakinannya akan sesuatu “yang takterjawantahkan” pada
ungkapan seni. Keyakinan ini pula yang membawa Lyotard
pada keadaan bahwa tidak pernah ada yang “diluar” atau
“yang lain”. Perbedaan antara “modern” dan “postmodern”
bagi Lyotard hanya ada pada pengakuan pada”yang
takterjawantahkan” dan tampilan. Estetika modern dan
estetika postmodern masing-masing sama dalam memiliki
daya ledak avant-garde namun yang pertama tidak berhasil
dalam tampilan. Sebab utamanya adalah adanya
kecendrungan naratif untuk membuat sistem satu bahasa
melalui legitimasi ilmiah.
Estetika dalam seni dan berkesenian tidak dapat diikat
dalam satu sistem bahasa. Selain mengandung kapasitas yang
takternalarkan dan terwujudkan, seni juga memiliki daya
ledak yang mampu membuat peristiwa. Karena itu, seni
hendaknya, menurut Lyotard, tidak menyesuaikan diri
dengan keadaan. Seni seharusnya mengikuti daya energiknya
untuk mencapai keluhuran (sublim).
Kesimpulan Dari paparan singkat diatas, jelaslah bagi kita bahwa
postmodernisme terutama dalam pemikiran Jean Francois
Lyotard ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap
grand narratives (narasi besar) dan lahirnya banyak mini
narratives (narasi kecil). Menurutnya, sebuah teori yang
72
berlaku dan sesuai pada suatu tempat dan masa tertentu tidak
dapat digeneralisasikan untuk tempat dan masa yang lain.
Disamping itu, postmodernisme menurut Lyotard juga
mencoba menghadirkan realitas yang majemuk dan
memberikan banyak alternatif. Warisan budaya modern yang
dikhotomistik hitam putih telah melahirkan kekakuan berfikir
yang pada gilirannya membuat orang terjebak dalam jurang
esensialisme universalisme. Cara berfikir seperti itu adalah
bentuk lain dari totalitarianisme, suatu paham yang menurut
Lyotard sudah tidak cocok dan relevan lagi dengan era
teknologi informasi.
Lyotard menolak kebenaran yang obyektif universal
karena menurutnya klaim kebenaran itu terbentuk dari
wacana (bahasa), kita tidak bisa menafsirkan realita yang
bebas dari bahasa. Semua kebenaran pemikiran berkaitan erat
dengan faktor sosial-budaya atau dengan permainan bahasa
tertentu.
73
MODERNISASI PEDESAAN (Meninjau kembali konsep modernisasi pedesaan)
Tri Yatno
Beberapa waktu yang lalu, ketika melakukan sebuah
penelitian di desa Pare Kabupaten Kediri saya sangat takjub
dengan fenomena yang bisa kita dapatkan disana, semisalkan
Pare yang sebelumnya kita pahami serta yang digambarkan oleh
Geertz sebagai sebuah desa ternyata bukan lagi desa yang kita
pahami dengan segala homogenitasnya namun berbalik menjadi
masyarakat yang sangat heterogen seperti kita pahami
karakteristik masyarakat perkotaan. Sepintas bukanlah sesuatu
yang aneh mengamati ragam karakteristik yang dimiliki oleh
mereka, beragamnya aliran kepercayaan, jenis pekerjaan serta
74
kemajemukan pendatang membuat kajian tentang pedesaan
tidak relevan lagi untuk dipakai.
Berangkat dari fenomena yang kita dapatkan di Pare,
sebenarnya ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji salah
satunya yaitu kondisi desa yang lebih menyerupai kehidupan di
kota. Seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli Sosiologi
tentang perkotaan yang akan mengalami dinamika sosial yang
lebih cepat akibat faktor perkembangan teknologi serta
informasi. Kota selayaknya kumpulan heterogenitas,
multikulturalis serta keterbukaan mencerminkan masyarakat
Pare seperti layaknya kontur kota kecil yang bergerak maju.
Namun sayangnya di Indonesia kita masih terjebak dengan
standar administrative yang menjadikan Pare tidak lebih hanya
desa kecil yang berpenghuni sedikit.
Dalam kacamata Sosiologi, desa berubah menjadi kota
lebih disebabkan karena masyarakat tersebut mengalami
perubahan yang lebih dikenal dengan nama berproses. Seperti
yang dikemukakan oleh Piotr Sztompka, “masyarakat
senantiasa berubah disemua tingkat kompleksitas internalnya.
Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik dan kultur.
Di tingkat mikro terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan
perilaku individual” (Sztompka, 2011).
Artinya konsekuensi dari perubahan sosial itu sendiri
adalah terjadi proses transformasi nilai yang sering diistilahkan
dengan modernisasi. Perubahan sosial pedesaan terjadi hampir
di seluruh pedesaan di Indonesia, terutama pedesaan dengan
basis pertanian padi sawah. Pada pedesaan-pedesaan ini
ketergantungan terhadap pihak luar (pemerintah dan Pasar)
semakin besar. Sedikit dari pedesaan-pedesaan di Indonesia
yang masih bertahan dengan sistemnya ini dan cenderung
membatasi diri dari tekanan modernisasi.
MEMAHAMI DESA YANG KE-INDONESIAAN Subtansi dari desa-desa di Indonesia digambarkan
dengan kekerabatan, banyak ahli yang mencirikan desa
dengan konstruksi pola kekerabatan yang sangat kuat
75
sehingga kekerabatan tersebut mampu mengikat setiap
individu yang berada di dalam lingkungan tersebut. Namun
sayangnya banyak referensi kemudian berkutat hanya dipulau
Jawa dan sering melupakan karakteristik desa-desa yang
berada jauh di barat maupun paling timur Indonesia.
Desa di Indonesia pada umumnya memiliki ciri-ciri
yang homogen dan natural namun tidak serta merta kita
menyamakan hal tersebut pada semua wilayah, desa memiliki
jumlah penduduk yang terbatas, interaksi yang intensif,
ikatan emosional yangkuat serta mereka memiliki pola pikir
yang tidak integritas. Desa memiliki daya ikat tersendiri
dimana mereka lebih banyak memiliki ikatan kekeluargaan
dan adanya lembaga-lembaga sosial desa yang ikut berperan
sebagai fasilitator untuk kemajemukan yang mereka miliki.
Masyarakat desa di Indonesia itu memang dapat kita
pandang juga sebagai suatu bentuk masyarakat yang
ekonomis terbelakang dan yang harus dikembangkan dengan
berbagai cara (Sajogyo 1990). Hal tersebut lebih disebabkan
oleh karena mainstream masyarakat kita yang selalu
menggambarkan desa sebagai wilayah yang dianggap
memiliki banyak kekurangan, mulai dari segi pendidikan,
kesehatan, pekerjaan sampai hiburan, factor inilah yang
kemudian menyebabkan terjadinya urbanisasi serta hilangnya
kemandirian masyarakat yang mendiami desa tersebut. Hal
ini terjadi salah satu faktornya karena pola pembangunan di
Negara kita yang selalu mengganggap desa sebagai penopang
derah perkotaan maka yang terjadi adalah desa menjadi pusat
lumbung bagi masyarakat kota.
Dalam pengertian administrative kita dapat menjumpai
berbagai jenis desa, misalkan berdasarkan topografi desa
dibagi menjadi; desa pegunungan, desa dataran rendah, desa
dataran tinggi, desa pantai. Lain halnya dengan desa
berdasarkan polapertanian; desa petani sawah, kampong
peladang, desa perkebunan rakyat, desa nelayan (Sediono,
1998).
76
Banyak desa yang kemudian tidak bisa kita masukan
kedalam 2 (dua) tipologi tersebut, sebut saja desa yang
orbitrasinya sangat kuat dengan perkotaan sebagai contoh
desa Ngringo di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Desa
yang secara Sosiologis sudah tidak lagi berkontur desa
melainkan kota kecil dengan konsekuensi interaksi dan pola
pikir masyarakat yang terlalu jauh dari defenisi Sosiologi itu
sendiri.
Ciri lain dari desa dalah petani dan padi, desa selalu
dikaitkan dengan petani dan padi sekalipun desa tersebut
sudah sangat sempit lahan untuk pertaniannya. Hal ini yang
mengidentikan desa dengan pekerjaan pertanian padahal
tidak semua desa saat ini memiliki lahan pertanian yang
memadai untuk beraktifitasnya para petani, namun masih saja
desa selalu di identikan demikian, mat saya ketika desa
diidentifikasikan dengan petani lebih disebabkan oleh
pekerjaan yang ditekuni sebab petani hanya mampu
beraktualisasi di desa yang sangat terbatas teritorialnya
sehingga universalisasi terhadap okupasi di desa adalah
petani, selain itu padi menajdi simbol untuk memaknai
sebuah desa ada dua penyebab utamanya yaitu kajian-kajian
pedesaan lebih banyak dilakukan di pulau Jawa dengan
komoditas utamanya padi yang kedua, padi merupakan
tanaman pokok yang selalu dikembangkan sebagai komoditas
unggulan yang selalu dianggapnya berasal dari wilayah
pedesaan. Maka tak ayal lagi desa akan selalu digambarkan
dengan dua hal tersebut.
Sudah saatnya kita (pemerintah, peneliti dan
stakeholder desa) harus memikirkan ulang kajian-kajian
untuk pedesaan artinya apa yang tergambar oleh masyarakat
diluar desa akan menjadi pijakan atau pedoman umum untuk
mengembangkan desa itu sendiri padahal yang tergambar
oleh kita bukanlah subtansi dari keadaan desa yang
sebenarnya. Desa bukan lagi menjadi territorial yang
didedefisikan dengan keterbelakangan pendidikan,
kemiskinan, atau bahkan menggambarkan desa sebagai
77
subsector yang berfungsi hanya sekedar untuk mendukung
ekonomi perkotaan, inilah yang banyak dikritik oleh ahli
pedesaan sebagai marjinalisasi orang desa.
Perkembangan pedesaan tidak terlepas dengan proses
modernisasi, yang dianggap mendatangkan perubahan dalam
sisi ekonomi masyarakat desa, banyak kajian serta penelitian
yang mengelaborasi proses modernisasi sebagai factor
pengembangan serta factor induk yang menyebabkan
berkembangnya desa.
KONSEKUENSI MODERNISASI Kunci dari sebuah proses modernisasi adalah
transformasi, factor penting dalam modernisasi adalah
terjadinya perubahan dalam masyarakat. Modernisasi tidak
akan terjadi jika perubahan masyarakat tidak terjadi. Inilsh
yang kemudian menjadi kunci-kunci pokok ketika kita akan
memahami sebuah modernisasi. Memahami modernisasi
tidak sekedar memahami perubahan yang terjadi saat ini
namun kembali kita pahami proses panjang yang
menyertainya sehingga akan kita pahami keseluruhan dari
modernisasi itu tersebut.
Menurut Eisenstadt, menurut sejarahnya, modernisasi
merupakan proses perubahan menuju tipe sistem sosial,
ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa dan Amerika
Utara dari abad ke-19 dan 20 meluas ke Negara-negara Amerika
Selatan, Asia serta Afrika (M.Francis Abraham, 1991), maka
bila kita bandingkan dengankondisi bangsa kita yang baru
mengecap kemerdekaan di akhir tahun 1945 apa kemudian kita
bisa menyamakan persepsi modernisasi yang dialami oleh
Negara-negara Eropa khususnya bagi mereka yang telah
memiliki kondisi yang jauh lebih baik tidak serta merta
kemudian kita konsumsi sebagai materi mengukur proses
modernisasi yang terjadi di Negara kita.
Mengungkap konsekuensi dari sebuah modernisasi
tidaklah mudah seperti yang dikemukakan oleh banyak ahli
social salah satunya, Industrialisasi, urbanisasi dan sekularisasi
78
pada umumnya dianggap sebagai proses yang menghasilkan
kondisi yang mendukung modernisasi, dan teknologi maju
dipandang sebagai suatu prasyarat pokok (M.Francis Abraham,
1991). Selain itu menurut prof DR. Selo Soemarjan (1986),
masyarakat akan mengalami tahap-tahap modernisasi yang
terjadi dihadapannya, yaitu tahapan paling rendah ketingkat
yang lebih tinggi. Adapun modernisasi yang dibagi menjadi
beberapa bagian; modrnisasi tingkat alat, modernisasi tingkat
lembaga, modernisasi tingkat individu, modernisasi tingkat
inovasi.
Terjadinya transformasi yang dianggap radikal dikaitkan
dengan bangkitnya jenis-jenis produksi industry mekanis dan
berskala besar. Penghapusan kerja berbasis agrarian yang terkait
dengan tanah, penghancuran komunitas desa yang terjalin kuat.
Semua ini merupakan bahagian besar konsekuensi dari
modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses transformasi
besar masyarakat, suatu perubahan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat, istilah yang paling spektakuler dalam
suatu masyarakat meliputi perubahan-perubahan tekhnik
produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern (Agus
salim, 2002).
Kajian modernisasi di pedesaan akan melahirkan
konsekuensi yang beguitu dominan antara proses yang
direncanakan serta yang tidak direncanakan, atau lebih
sederhananya dampak langsung dan tidak langsung. Ada
beberapa hal yang bisa penulis kemukakan sebagai konsekuensi
dari masalah tersebut yaitu; bergesernya nilai dan norma dalam
tatanan kehidupan, berubahnya fungsi lembaga lembaga social,
berubahnya nilai fungsi lahan desa serta berubahnya pola
okupasi masyarakat desa.
Nilai dan norma masyarakat desa akan bergeser ketika
pola pikir masyarakat desa yang sebelumnya sangat dekat pola
keagamaan akan beralih pada rasionalitas yang diakibatkan oleh
tingkat pendidikan dan tranformasi media serta interaksi dengan
masyarakat sekitar. Apa yang diakibatkan adalah berubahnya
gaya hidup masyarakat dipedesaan. Kita tidak mungkin
79
mengurai sampai tuntas nilai dan norma yang harus berubah
namun setidaknya orang desa akan punya standarisasi tersendiri
ketika mereka mengukur sebuah perilaku, strata, mapun
interaksi yang ada. Tendensi dan standart terbangun akibat
pendidikan yang mereka miliki merubah gaya berpikir serta
media yang selalu menyajikan tayangan yang dapat membentuk
cara dan kebiasaan baru mereka dalam menilai maupun
memutuskan sesuatu. Gaya yang identik dengan sakral berganti
dengan rasionalisasi, hal-hal gaib tergeser oleh adanya
kenyataan yang ditampilkan oleh rasio.
Unsur lainnya yang dipengaruhi oleh modernisasi yaitu
keberadaan lembaga-lembaga yang berada di desa, pada
muasalnya lembaga di desa berfungsi sebagai mediator
kepentingan masyarakat dengan alam, masyarakat dengan
leluhur dan antar mereka sendiri. Namun yang terjadi adalah
lembaga sebagai penyalur aspirasi dari elitedesa maupun tokoh
yang berpengaruh di desa tersebut maka fungsi yang
tadinyasebagai mediator berubah menjadi pragmatis dengan
atribut kepentingan individu maupun kelompok yang dominan
di desa.
Tidak terlepas dari itu semua, factor yang cukup dominan
mengalami perubahan adalah beralihnya fungsi lahan di
pedesaan, yang sebelumnya banyak berfungsi untuk ditanami
tanaman pertanian kini lebih banyak dikelola sebagai lahan
industry maupun tanaman industri. Kondisi lahan seperti ini
banyak terjadi akibat letak geografis desa yang dekat dengan
kota sehingga lahan yang asal mulanya sebagai sumber
penghidupan bergeser menjadi sumber lahan untuk pengolahan.
Pabrik, atau industri bahan baku banyak dikembangkan di lahan
pertanian dengan perhitungan lebih murah bila dibandingkan
dengan lahan di perkotaan, selain itu tanaman industri juga ikut
merubah corak fungsi lahan yang sebelumnya mengaitkan
banyak pihak di desa menjadi sebuah konsorsium yang diikat
dengan perjanjian yang sangat kaku.
Alhasil, dengan menyempitnya lahan-lahan pertanian di
pedesaan masyarakatpun mulai berpikir untuk mencari
80
pekerjaan lain, seperti halnya yang banyak kita temui bahwa
petani kemudian beralih menjadi buruh pabrik, buruh industri
bahkan pedagang yang lokasi bekerjanya di luar desa tempat
dimana mereka tinggal. Hal ini kemudian menjadi sangat
rasional ketika kita bandingkan pengurangan lahan dengan
ketersediaan jumlah tenaga kerja belum lagi di tambha dengan
keahlian yang harus di miliki oleh mereka ketika masuk pada
pola pekerjaan yang tergolong modern.
Apa yang dapat kita simpulkan dari konsekuensi yang
harus diterima oleh sebuah desa ketika harus mengalami yang
namanya modernisasi, bahwa tatanan yang pernah mengatur
mereka dalam pola kehidupan masyarakat desa menjadi
berubahmenjadi tatanan yang diatur oleh kebutuhan akibat
terjadinya proses modernisasi.
MODERNISASI DESA UNTUK KESEJAHTERAAN
Modernisasi bukanlah sesuatu yang keliru untuk
dikembangkan, pada intinya modernisasi lebih menunjuk pada
suatu tranformasi dalam kerangka pencapaian kesejahteraan
kehidupan manusia, kita kemudian dapat mengambil apa yang
berfungsipositif bagi kita semua dan dapat mengevaluasi
sesuatu dampak yang kiranya bersifat negative bagi kehidupan
kita semua.
Memodernisasikan desa adalah proses dimana kita secara
sengaja mentransformasikan segala bentuk perubahan yang
sifatnya kompleks untuk membentuk ataupun menyempurnakan
kehidupan pada masyarakat desa. Contoh yang bisa diambil
yaitu bagaimana kemudian pola pertanian di desa dapat
mengalami peningkatan yang sebelumnya sangat terantung oleh
alam dan dapat kita rubah dengan teknologi, system tanam
maupun pola distribusi hasil pertanian itu sendiri. Atau juga kita
kembangkan pola ekonomi desa yang lebih fleksibel dengan
menggunakan jaringan internet atau media social untuk
pemasarannya, artinya kita menggunakan hasil teknologi yang
ada untuk memasarkan hasil produksi kita.
81
Memodernisasikan desa bukan berarti menghancurkan
atau menghilangkan apa yang telah ada sebelumnya dengan
sesuatu yang baru namun kita bisa mengkolaborasikan yang
sebelum dengan yang baru sebagai sesuatu yang lebih efisien
dan bersifat membangun.
82
DUALISME EKSISTENSI KONDOM;
DALAM KAJIAN HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA
M. Chairul Basrun Umanailo
Bagi sebagian orang, kondom merupakan alat yang
sering dijadikan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya
untuk pengendalian jumlah anak, penyebaran virus HIV serta
sebagai pendukung profesi yang sementara ditekuni. Namun di
lain pihak ada juga yang kemudian mempertanyakan kembali
kondom sebagai alat kontrasepsi untuk pengendalian masuknya
sperma ke Rahim perempuan karena dianggap memiliki
dampak yang kurang baik bagi mereka yang memiliki tafsir
83
tersendiri atas eksistensi kondom, artinya kondom juga dapat di
jadikan sebagai komoditi transaksional dalam suatu tindakan
manusia.
Mengkaji kondom, berarti kita harus berhadapan dengan
dua perspektif berbeda, oleh karena diantara dua perspektif
tersebut memiliki landasan berpikir yang sulit disatukan.
Hukum agama dan hukum Negara adalah dua mata pisau yang
berbeda untuk menyelesaikan persoalan kondom, hukum agama
sendiri lebih melihat kondom sebagai alat yang menghalalkan
sebuah tindakan yang dilarang oleh agama sementara hukum
Negara sendiri melindungi kondom sebagai alat yang mampu
menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakatnya dalam hal
ini pengendalian penduduk dan penyebaran virus HIV. Maka
tak bisa dipungkiri diantara dua perspektif tersebut memiliki
landasan logika yang rasional serta tertanggung jawab untuk
tetap mempertahankan serta melarang eksistensi kondom itu
dalam masyarakat.
Kondom adalah alat kontrasepsi untuk mencegah
kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat
bersenggama, kondom biasanya dibuat dari bahan karet latex
dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan
ereksi sebelum bersanggama (bersetubuh) atau berhubungan
suami istri. Kondom tidak hanya dipakai oleh lelaki, terdapat
pula kondom wanita yang dirancang khusus untuk digunakan
oleh wanita.
Kondom ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke
dalam alat kelamin atau kemaluan wanita. Cara kerja kondom
wanita sama dengan cara kondom lelaki, yaitu mencegah
sperma masukke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat,
keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom
wanita, hampir sama dengan kondom lelaki. Tingkat efektifitas
kondom wanita akan tinggi, apabila cara menggunakannya
benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit
yaitu 2-12 kehamilan per/100 perempuan per tahun
(wikipedia.org).
84
Kata kondom diambil dari nama Dr.Condom, seorang
dokter asal Inggris yang bergelar Pangeran. Pada pertengahan
tahun 1600, ia yang mula-mula mengenalkan corong untuk
menutupi penis untuk melindungi King Charles II dari
penularan penyakit kelamin. Menurut Charles Panati, dalam
bukunya Sexy Origins and Intimate Things, sarung untuk
melindungi penis telah dipakai sejak berabad silam. Sejarah
menunjukkan orang-orang Roma, mungkin juga Mesir,
menggunakan kulit tipis dari kandung kemih dan usus binatang
sebagai "sarung".
Kondom primitif itu dipakai bukan untuk mencegah
kehamilan tapi menghindari penyakit kelamin. Untuk menekan
kelahiran, sejak dulu pria selalu mengandalkan kaum
perempuan untuk memilih bentuk kontrasepsi. Adalah Gabriello
Fallopia, dokter dari Italia yang hidup di abad ke-17 yang
pertama kali menjelaskan dua tabung pipih yang membawa sel
telur dari ovarium ke uterus. Ia dikenal sebagai "bapak kondom"
karena pada pertengahan tahun 1500 ia membuat sarung linen
yang berukuran pas (fit) di bagian penis dan melindungi
permukaan kulit. Penemuannya ini diuji coba pada 1000 pria
dan sukses. Kondom di abad 17 berbentuk tebal dan dibuat dari
usus binatang, selaput ikan atau bahan linen yang licin. Namun
karena kondom dipandang mengurangi kenikmatan seksual dan
tidak selalu manjur mencegah penularan penyakit (akibat
penggunaan berulang kali tanpa dicuci), kondom pun menjadi
tidak populer dan jadi bahan diolok-olok. Seorang bangsawan
Perancis bahkan menyebut kondom sebagai "tameng melawan
cinta, sarung pelindung dari penyakit" (Kompas.com).
Dari catatan sejarah kondom telah digunakan sejak
beberapa ratus tahun yang lalu. Sekitar tahun 1000 sebelum
Masehi orang Mesir kuno menggunakan linen sebagai sarung
penganan untuk mencegah penyakit. Pada tahun 100 sampai
tahun 200 Masehi bukti awal dari pemakaian kondom di Eropa
datang dari lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles,
Prancis. Tahun 1500-an untuk pertama kali dipublikasikan
deskripsi dan pencobaan alat mencegah penyakit berupa
85
kondom di Italia. Ketika itu Gabrielle Fallopius mengklaim
menemukan sarung terbuat dari bahan linen dan itu diuji coba
pada 1.100 lelaki sebagai kondom. Dari percobaan itu tak satu
pun dari mereka yang terinfeksi penyakit sifilis. Penemuan
membuktikan bahwa kain linen itu bermanfaat mencegah
infeksi. Tetapi, di kemudian hari kondom dikenal sebagai alat
mencegah kehamilan. Itu diawali dari percobaan terhadap kain
linen yang dibasahi dengan cairan kimia tahun 1500-an. Ketika
linen direndam dalam cairan kimia kemudian dikeringkan dan
dikenakan pria maka kain itu bisa mematikan sperma.
Tahun 1700-an, kondom dibuat dari usus binatang.
Perubahan bahan itu membuat harga kondom menjadi lebih
mahal dibanding dengan kondom dari bahan linen. Ketika itu
kondom dikenal sebagai 'baju baja melawan kesenangan dan
jaring laba-laba mencegah infeksi. Kondom tipe itu dipakai
secara berulang.
Tahun 1894, Goodyear dan Hancock mulai memproduksi
kondom secara massal terbuat dari karet yang divulkanisasi
untuk membalikkan karet kasar keelastisitas yang kuat. Tahun
1861 untuk pertama kali kondom dipublikasikan diamerika
Serikat di surat kabar The New York Times. Tahun 1880
kondom dibuat dari lateks, tetapi pemakaiannya secara luas baru
tahun 1930-an. Tahun 1935 sebanyak 1.5 juta kondom
diproduksi setiap hari di Amerika Serikat. Kemudian tahun
1980-an dan 1990-an pasaran kondom di Amerika Serikat
didominasi pabrik kondom setempat. Baru tahun 1987 kondom
produksi Jepang dengan merek Kimono memasuki pasar
Amerika. Kondom tersebut lembut tipis dan iklannya pun
menekankankan bahwa kesenangan sama pentingnya dengan
pencegahan. Tahun 1990-an muncul beragam jenis kondom dan
juga untuk pertama kali tersedia kondom polyurethane. Tahun
1993 produksi tahunan kondom lateks mencapai 8,5 juta miliar
(www.sikondom.com/images). MENGINTEPRETASI KONDOM LEWAT KAJIAN ISLAM
Ada baiknya kita melihat lebih jauh kondom dari
perspektif agama sehingga jelas kiranya bagi kita semua
86
memaknai eksistensi kondom di tengah-tengah masyarakat saat
ini. Dalam kehidupan beragama ada anjuran untuk
memperbanyak keturunan, Dari Ma‟qil bin Yasar al-Muzani
radhiyallahu „anhu dia berkata:
Seorang lelaki pernah datang (menemui) Rasulullah
shallallahu „alaihi wa sallam dan berkata: Sesungguhnya
aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki
kecantikan dan (berasal dari) keturunan yang terhormat,
akan tetapi dia tidak bisa punya anak (mandul), apakah aku
(boleh) menikahinya? Rasulullah shallallahu „alaihi wa
sallam menjawab: “Tidak (boleh)”, kemudian lelaki itu
datang (dan bertanya lagi) untuk kedua kalinya, maka
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam kembali
melarangnya, kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi)
untuk ketiga kalinya, maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa
sallam bersabda: “Nikahilah perempuan yang penyayang
dan subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan
membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan
umat-umat lain (pada hari kiamat nanti).” Bagi seorang
perempuan yang masih gadis. Kesuburan ini diketahui
dengan melihat keadaan keluarga (ibu dan saudara
perempuan) atau kerabatnya, lihat kitab „Aunul Ma‟buud,
6/33-34) (HR Abu Dawud (no. 2050), an-Nasa-i (6/65) dan
al-Hakim (2/176), dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4056-
al-Ihsan), juga oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-
Dzahabi).
Hadits ini menunjukkan keutamaan memiliki banyak
keturunan yang diberkahi Allah ta‟ala, karena Rasulullah
shallallahu „alaihi wa sallam tidak mungkin mendoakan
keburukan untuk sahabatnya, dan Anas bin Malik radhiyallahu
„anhu sendiri menyebutkan ini sebagai doa kebaikan. Oleh
karena itulah, imam an-Nawawi mencantumkan hadits ini
dalam bab: keutamaan Anas bin Malikradhiyallahu „anhu.
(Lihat Syarah Shahih Muslim, 16/39-40)
Hukum asal membatasi atau mengatur jumlah keturunan
(baca: Keluarga Berencana) dalam Islam adalah diharamkan,
87
karena menyelisihi petunjuk syariat Islam yang melarang keras
perbuatan tabattul (hidup membujang selamanya) (Dalam hadits
shahih Riwayat Ahmad (3/158 dan 3/245) dan Ibnu Hibban (no.
4028), dishahihkan oleh syaikh al-Albani dalam Irwa-ul Ghalil
(6/195)), dan memerintahkan untuk menikahi perempuan yang
subur (banyak anak). Oleh karena itu, mengonsumsi pil
pencegah kehamilan atau obat-obatan lainnya untuk mencegah
kehamilan tidak diperbolehkan (dalam agama Islam), kecuali
dalam kondisi-kondisi darurat (terpaksa) yang jarang terjadi
(Fatawa Lajnah Daaimah (19/319) no (1585) yang dipimpin
oleh syaikh „Abdul „Aziz bin Baz, dengan sedikit penyesuaian).
Membatasi keturunan dengan tujuan seperti ini dalam
agama Islam diharamkan secara mutlak, sebagaimana
keterangan Lajnah daaimah yang dipimpin oleh Syaikh „Abdul
„Aziz bin Baz (Fatawal Lajnatid Daaimah, (9/62) no (1584)),
demikian juga Syaikh Muhammad bin Shaleh al-‟Utsaimin
(Silsilatu Liqa-aatil Baabil Maftuuh, (31/133)), syaikh Shaleh
al-Fauzan (Al-Muntaqa Min Fatawa al-Fauzan (69/20)) dan
Keputusan majelis al Majma‟ al Fiqhil Islami (Majallatul
Buhuutsil Islaamiyyah(30/286). Karena ini bertentangan dengan
tujuan-tujuan agung syariat Islam, seperti yang diterangkan di
atas.
Mencegah kehamilan adalah menggunakan berbagai
sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang
perempuan dari kehamilan, seperti: al-‟Azl (menumpahkan
sperma laki-laki di luar vagina), mengonsumsi obat-obatan
(pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina,
menghindari hubungan suami istri ketika masa subur, dan
yang semisalnya (Fatwa Haiati Kibarul „Ulama‟ (5/114 –
Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah)). Pencegahan kehamilan
seperti ini juga diharamkan dalam Islam, kecuali jika ada
sebab/alasan yang (dibenarkan) dalam syariat.
Dalam fatwa Lajnah Daimah: “…Berdasarkan semua
itu, maka membatasi (jumlah keturunan) diharamkan secara
mutlak (dalam Islam), (demikian juga) mencegah kehamilan
diharamkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang
88
jarang (terjadi) dan tidak umum, seperti dalam kondisi yang
mengharuskan wanita yang hamil untuk melahirkan secara
tidak wajar, dan kondisi yang memaksa wanita yang hamil
melakukan operasi (caesar) untuk mengeluarkan bayi (dari
kandungannya), atau kondisi yang jika seorang wanita hamil
maka akan membahayakannya karena adanya penyakit atau
(sebab) lainnya. Ini semua dikecualikan dalam rangka untuk
menghindari mudharat (bahaya) dan menjaga kelangsungan
hidup (bagi wanita tersebut), karena sesungguhnya syariat
Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)
dan mencegah kerusakan… (Majallatul Buhuutsil
Islaamiyyah (5/127).
Mengatur kehamilan adalah menggunakan berbagai
sarana untuk mencegah kehamilan, tapi bukan dengan tujuan
untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat
reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam
jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya
maslahat (kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat) yang
dipandang oleh kedua suami istri atau seorang ahli (dokter)
yang mereka percaya (Fatwa Haiati Kibarul „Ulama‟
Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah) (muslim.or.id/akhlaql). NALAR HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KONDOM
Bergeser dari pengendalian jumlah penduduk, pada
orde reformasi kondom lebih diaktualisasikan sebagai
penghambat laju HIV-AIDS karena bagi pemerintah tidak
sekedar wacana akan bahayanya AIDS jauh lebih praktis
dengan menyediakan alat untuk mengatasinya. Pemerintah
dari berbagai sektor terus mempromosikan pentingnya
penggunaan kondom untuk pencegahan penyebaran virus
HIV sehingga tanpa ruang yang tersekat hamper seluruhnya
dipakai untuk mempropagandakan masalah penggunaan
kondom.
Tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Kesehatan
oleh Presiden, Nafsiah Mboi langsung menggebrak publik
dengan rencananya melakukan sosialisasi dan kondomisasi
terhadap kelompok seksual beresiko, termasuk kepada
89
kelompok remaja dengan perilaku seksual beresiko. Yang
dimaksud kelompok dengan perilaku seksual beresiko, antara
lain pelacur, pria hidung belang, buruh di pelabuhan,
nelayan, pelaut, termasuk kelompok gay dan waria.
Rencana sosialisasi dan pembagian kondom kepada
khalayak dengan perilaku seksual tidak sehat dan beresiko
sempat menjadi berita besar di masyarakat dan media massa.
Namun akhir-akhir ini, seakan redup, kalau tidak dikatakan
hilang. Padahal rencana sudah digodog matang dan siap
untuk diluncurkan ke masyarakat sebagai kebijakan Menkes
yang baru. “Kampanye kondom bukan sembarang kampanye.
Itu adalah salah satu indikator dalam mdgs poin 6, yaitu
penggunaan kondom pada seks beresiko.
Jadi itu kewajiban kami untuk mengampanyekan
kondom pada seks beresiko,”. Secara yuridis pun, penulis
melihat tidak ada dasar bagi Menkes untuk membuat
kebijakan kondomisasi ini. Payung hukum dibidang
kesehatan, yakni UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:
“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis”.
Sedang menurut Pasal 2 UU No. 36 tahun 2009
disebutkan bahwa:
“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan
berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,
perlindungan, penghormatan terhadap hak dan
kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan
norma-norma agama.” Penyelenggaraan upaya
kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan
norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.
90
Yang dimaksud dengan seks berisiko adalah setiap
hubungan seks yang beresiko menularkan penyakit dan atau
berisiko memicu kehamilan yang tidak direncanakan.
Kampanye ini menjadi penting, mengingat masih banyak
kasus kehamilan yang tidak direncanakan terjadi pada anak-
anak remaja. Sangat penting untuk melakukan pendekatan
kesehatan kepada masyarakat. Terutama untuk mencegah
agar tidak ada kehamilan yang terjadi karena tidak
direncanakan. Karena itu, kita menyasar terutama pada usia
15-24 tahun.
Undang-Undang yang menyatakan yang belum
menikah tidak boleh diberikan kontrasepsi sudah tidak
relevan. Pemerintah berharap bisa meningkatkan kesadaran
mengenai kesehatan reproduksi untuk remaja. Dalam
undang-undang, yang belum menikah tidak boleh diberi
kontrasepsi. Namun ketika menganalisis data dan itu ternyata
berbahaya jika tidak melihat kenyataan. Sebanyak 2,3 juta
remaja melakukan aborsi setiap tahunnya menurut data dari
BKKBN.
Angka sebanyak itu menunjukkan bahwa banyak
remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ia
menegaskan, undang-undang perlindungan anak menyatakan
bahwa setiap anak yang dikandung sampai dilahirkan harus
diberikan haknya sesuai Undang-Undang Perlindungan
Anak. Maka, mempermudah akses remaja untuk
mendapatkan kondom diharapkan dapat menekan angka
aborsi dan kehamilan yang tak diinginkan
(www.arrahmah.com).
DAMAI UNTUK KONDOM
Kondom dalam pandangan Sosiologi Hukum
merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi mengendalikan
perilaku individu maupun kelompok, dalam artian kondom
mampu menjadi alat pengontrol bagi seseorang dalam
perilaku seksual nya. Namun dibalik itu semua ada hal-hal
91
penting yang menjadi nilai control itu berubah menjadi nilai
perilaku bagi seseorang ketika mengintepretasikan kondom.
Mengkaji perilaku individu Secara mendasar, paling
tidak ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku
menyimpang, yaitu absolutist, normative, dan reaktive.
Perspektif absolutist; berpendapat bahwa kualitas atau
karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik,
terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku
menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan,
atau aturan-aturan sosial. Perspektif normative; berpendapat
bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai
setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan
kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam
masyarakat (Cohen, 1992: 218).
Konsepsi yang bisa kita simpulkan bahwa dengan
keberadaan kondom maka akan membuka kesempatan untuk
terjadinya perilaku menyimpang, akibat perilaku yang
dihasilkan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat secara
umum. Penyebab utamaa dari hal demikian adalah
ketidaksesuaian antara hukum Negara dengan aturan-aturan
yang dipegang oleh kelompok yang ada dalam masyarakat
yakni masyarakat muslim. Berkaitan dengan perilaku
menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang
termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah
memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk
dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab
terjadinya perilaku menyimpang.
Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya tentang
anomie, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta
akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan
sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkkan
anomie dengan penyimpangan social. Lebih lanjut ia
berpendapat bahwa sebagai akibat dari proses sosialisasi,
individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan
dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan
tersebut yang selaras dengan kebudayaan.
92
Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang
selaras dengan kebudayaan tidak ada atau tidak mungkin
dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau
cara alternative, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai
perilaku menyimpang.
Merton menyebutkan ada empat perilaku menyimpang,
yaitu inovasi (innovation), ritualism (ritualism), peneduhan
hati (retreatism), dan pemberontakan (rebellion) Bahwa
kondom sebagai pengendali perilaku menyimpang juga bisa
sepakati namun akan tumbuh bersama dengan perilaku
menyimpang lainnya. Artinya ketika kondom dijadikan alat
untuk menutupi perilaku menyimpang, maka orang akan
mengkonstruksikan perilaku tersebut pada tahapan yang lebih
jauh lagi seperti misalkan kebiasaan dan menjadi budaya
baru.
93
DOMINASI MODAL EKONOMI ATAS RANAH POLITIK
M. Chairul Basrun Umanailo
Menjelang pelaksanaan Pemilu, tentunya banyak pihak
akan menghitung ulang modal yang tersisa untuk bertarung
pada malam menjelang pencoblosan. Mereka menaruh
harapan, bahwasanya sisa modal tersebut merupakan senjata
94
pamungkas yang bisa dipakai untuk mendulang sejumlah
suara yang diharapkan.
Tak dapat dipungkiri modal ekonomi menjadi sangat
begitu penting ketika ritual pemilihan umum berlangsung,
membuka daftar sumbangan ke partai sampai melihat
pesanan peraga kampanye kita akan berdesak kagum dengan
jumlah angkanya dan berandai-andai semisalkan dana
tersebut dibelanjakan untuk pembangunan MCK dan
beasiswa anak-anak bangsa ini. Namun inilah realitas politik
bahwa sementara waktu, kita lupakan dulu kenyataan yang
ada alasan pokok dan fungsional, bahwa modal ekonomi
lebih diartikan secara luas akan kemampuan seseorang dalam
kepemilikan serta pengaksesan kepada sumber-sumber
ekonomi maupun sumber daya yang tersedia.
Saya menghindar untuk menyamakan modal ekonomi
sama dengan modal kekayaan dan uang sebab secara
langsung akan melahirkan determinasi kelas penguasaan
kekayaan secara terstruktur berdasar jumlah yang dimiliki,
lebih lanjut bahwa modal seseorang untuk mengakses
sumber-sumber ekonomi inilah yang menjadi faktor lebih
dominan bila dibandingkan dengan kepemilikan sejumlah
materi yang bersifat ekonomi. Secara umum, Bourdieu
membedakan empat jenis modal: ekonomi, budaya, sosial,
dan simbolik. Meski berbeda, keempat bentuk modal ini bisa
saling dikonversikan dan diwariskan pada orang lain dengan
nilai tukar dan tingkat kesulitanyang berbeda. Masing-
masing jenis modal ini didapat dan diakumulasikan dengan
saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain
(Aunullah, 2006).
Bila kemudian kita konversikan dengan situasi
pemilihan legislative saat ini maka dominasi modal ekonomi
akan jauh lebih terlihat dibandingkan dengan modal-modal
lainnya tanpa harus mengesampingkan bahwa diantara
modal-modal tersebut saling memiliki ketergantungan yang
kuat. Mengapa kemudian modal ekonomi saya anggap jauh
lebih dominan, tentunya ada beberapa alasan penting untuk
95
mengutarakan hal tersebut yakni; (1) Masyarakat kita telah
terbentuk dengan logika konsumtif, (2) Pendekatan politik
lebih kepada pragmatism (3) tumbuhnya kesadaran semu
yang menciptakan masyarakat tanpa identitas. Bagi saya
ketiga hal tersebut yang kemudian membuka ruang yang
besar kepada modal ekonomi menjadi dominasi modal atas
ranah politik yang ada disaat ini.
Mari kita buktikan dengan kondisi yang terjadi saat ini,
bahwasanya setiap calon yang akan mengikuti ajang
pemilihan legislative entah pada tataran DPR RI hingga
DPRD akan dibebankan pada dua porsi yang horizontal yaitu
mereka harus membesarkan dominasi partai dalam
masyarakat dan sisi lainnya mereka juga harus mampu
mensosialisasikan diri mereka sendiri kepada konstituen yang
tersedia, artinya dibutuhkan paling tidak alat peraga seperti
stiker, spanduk, baliho untuk menyelesaikan beban tersebut,
kemampuan ekonomi (uang) menjadi ukuran melakukan
kegiatan ini.
Maka ranah politik (menjadi Anggota legislatif)
menjadi sangat sulit diakses oleh mereka yang memiliki
keterbatasan modal tersebut. Logika konsumtif Masyarakat
merupakan suatu relasi sosial yang paling terbesar, relasi
tersebut terbangun dengan beberapa metode seperti misalkan
hubungan emosional, hubungan kepentingan dan sebagainya.
Dengan konstruksi tersebut kita bisa memakai konsep yang
ditawarkan oleh Douglas dan Isherwood dalam feathersone
(1992:14) yang berpendapat, bahwa dalam masyarakat saat
ini barang-barang digunakan untuk membangun hubungan-
hubungan sosial.
Masyarakat telah terkonstruksi dengan pola konsumsi
yang disampaikan oleh Baudrillard bahwa masyarakat
berusaha menunjukan rasionalitas hidup yang senantiasa
berorientasi dan merujuk objek material danperubahan
paradigm ini membuat mereka terjebak dengan pemaknaan-
pemaknaan yang mereka ciptakan sendiri sebagai penanda.
Lebih lanjut dengan konstelasi politik yang pragmatis maka
96
masyarakat akan terhanyut pada pola pikir material yang
didapatkan untuk pengaksesan nilai politik dari orang yang
memberikan. Contoh konkrit yaitu dengan masuknya kita
pada fase kampanye banyak masyarakat melacurkan
identitasnya dengan berbagai sumbangan dan permohonan
untuk suatu material, kita tidak lagi malu-malu untuk
menyatakan “wani piro” pada hal konsekuensi yang harus
kita tanggung jauh lebih besar dari yang didapatkan saat itu.
Caleg membidik pemilih pemula dengan konser musik,
artinya dengan pendekatan tersebut pemilih pada kalangan
remaja dapat tertarik untuk memilihnya dan ini berhasil
ketika remaja kita adalah remaja konsumtif dengan
mengutamakan identitas sebagai remaja yang butuh
aktualisasi music. Kembali pada modal ekonomi bahwa
siapapun yang tidak memiliki modal ekonomi maka sulit
untuk masuk pada ranah politik praktis sebab masyarakat
tidak butuh hanya sekedaran penyadaran lewat dialog
maupun cara-cara cerdas lainnya.
Pendekatan Pragmatis Pendekatan politik yang pragmatis yaitu dengan
mengurai apa yang anda butuhkan dan apa yang dibutuhkan
konstituen anda. Orang kebanjiran tidak butuh penyadaran,
korban letusan gunung berapi tidak butuh sosialisasi politik,
namun yang dibutuhkan adalah materi (uang) untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Suka ataupun tidak calon
legislative harus mengeluarkan dana lebih untuk bisa
mendapatkan simpatisan dari masyarakat seperti ini. Modal
ekonomi sangat memiliki peranan saat bantuan yang anda
berikan hanya sebatas pemenuhan primer yang bukan jadi
harapan mereka. Dan hal ini kemudian menjadi rujukan bagi
mereka untuk memutuskan pilihan kepada siapapun, mereka
tidak bisa kita salahkan bila material yang menjadi
keberpihakan pada tataran pragmatis. Maka dominasi modal
ekonomi menjadi pertanyaan terbesar bilamana seseorang
ingin meraup keuntungan politik dari situasi seperti ini.
97
Kesadaran Semu Apa yang dikemukakan oleh Gramsci, Marx ataupun
Bourdieu tentang kesadaran semu dari masyarakat proletar
ini menjadi persoalan tersendiri bilamana kitakaitkan dengan
fenomena perpolitikan yang ada. Persoalannya bukan sekedar
mereka terkesploitiasi pada tataran produksi namun yang
terjadi adalah tereksploitasinya modal-modal ekonomi yang
ada pada masyarakat. Kita contohkan saja masyarakat “A”
bahwa mereka selama ini tereksploitasi akibat sumberdaya
alam yang dimiliki tidak mampu memberikan faedah bagi
kehidupannya, dengan adanya pesta demokrasi seperti
pemilihan legislative maka materi serta harapan yang
diberikan lebih oleh para calonakan menghilangkan sejenak
kesadaran akan tereksploitasinya mereka, sehingga bagi
Caleg strateginya dengan membawa logika “apa yang mereka
butuhkan” dengan konsekuensi pemenuhan kebutuhan
material. Material yang diberikan tentunya diiringi dengan
kemampuan finansial sang calon yang sangat besar.
Jadi, konektivitas ranah politik bagi seorang Caleg,
sangat tergantung dari akses serta kepemilikan modal
ekonomi mereka. Seperti yang dikemukan oleh Polanyi;
Pengaturan ekonomi manusia biasanya tertanam di dalam
hubungan sosialnya. Dia tidak bertindak demi menjaga
kepentingan individualnya dalam hal kepemilikan barang-
barang material; dia bertindak demi mengamankan
kedudukan social, hak-hak sosial, dan aset-aset sosialnya.
Dia menghargai barang-barang material hanya sejauh barang-
barang tersebut memenuhi tujuan tersebut (Polanyi, 2003
:62).
Dialektika ini yang melahirkan konsepsi dominasi
modal ekonomi pada suatu ranah politik, akibat masyarakat
yang terbangun dengan kesadaran primer (apayang saya
butuh) dan perilaku politik pragmatis. Konsekuensinya
adalah terciptanya masyarakat politik yang rapuh karena
terbangun dari pondasi-pondasi kepentingan struktur. Tanpa
harus saling menyalahkan siapa yang harus memulai
98
penyadaran, yang terpenting bagi kita adalah mengurangi
dominasi modal ekonomi terhadap perpolitikan di negara
kita, saya yakin suatu saat fenomena ini bisa kita dapatkan
ketika kesadarandan pola pikir kritis kita sudah terbentuk
pada tataran ideology, serta kita mampumen dekonstruksi
pola-pola pikir pragmatis material.
Pada prinsipnya masyarakat harus menyadari situasi
seperti ini, kita tidak kemudian menyerah dan terperangkan
dalam sebuah budaya yang pada akhirnya menciptakan
marjinalitas terhadap kehidupan kita sendiri. Masyarakat
perlu tahubahwasanya faktor ekonomi bukanlah sesuatu yang
urgen untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan sikap
berpolitik sebab akan melahirkan pragmatisme bagi mereka
dalam perpolitikan kita.
Di lain pihak, modal ekonomi adalah modal yang
sangat berpengaruh dalam kinerja berpolitik namun
kemudian jangan sampai mendominasi setiap gerakan
perpolitikan untuk meraup keuntungan yang belum jelas
angka-angkanya, masih banyak cara-cara serta strategi cerdas
untuk mendapatkan dukungan politik namun tidak sekedar
dengan nilai material yang kita miliki.
99
KEBIJAKAAN POLITIK PENDIDIKAN YANG MERAKYAT
M. Chairul Basrun Umanailo
PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai pilar bangsa merupakan cita-cita
pendahulu kita semenjak negara ini diberdirikan oleh para
pahlawan, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bukan
dimulai dengan letusan senapan api sebagaimana yang
dikonstruksikan lewat film-film bersejarah, namun
sebaliknya kemerdekaan itu diawali dengan pendidikan. Kita
sebut saja, Kartini, Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantoro dan
lain-lain. Mereka adalah tonggak kemerdekaan yang mampu
menjadi inspirasi perjuangan bagi bangsa Indonesia. Lewat
sejarah kita bisa membuktikan bahwa pendidikan adalah
senjata utama untuk merebut kemerdekaan, karena lewat
pendidikan orang mulai berpikir, merencanakan dan orang
akan berusaha untuk mencapai tujuannya, lewat bekal yang
ada di pikirannya. Sebab pendidikan mampu membangkitkan
kesadaran seseorang untuk melihat kehidupannya yang
terjadi pada saat itu.
Pendidikan adalah instrument penting dalam
membangun karakter bangsa (nation character building).
Disadari atau tidak, pendidikan juga merupakan investasi
jangka panjang suatu masyarakat-bangsa agar dapat
melangkah lebih baik menuju kehidupan yang lebih beradab
(civilized). Ibnu Khaldun mengatakan ;
“hanya di dalam realitas masyarakat yang memiliki
kesadaran akan pentingnyaperkembangan ilmu
pengetahuan dan pendidikan, maka peradaban dan
nilainilaibudaya konstruktif akan dapat ditegakkan.”
100
Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dimaknai
sebagai transfer of knowledge semata, akan tetapi yang lebih
mendasar ialah bahwa pendidikan merupakan lokomotif dan
dinamisator dalam perubahan masyarakat- bangsa (Tarmiji,
2014). Perkembangan pendidikan seharusnya searah dengan
perkembangan kehidupan bernegara, selarasnya pendidikan
menjadi nadir atas tumbuh kembangnya sebuah peradaban,
kita bisa belajar dari Jepang, Jerman dan bahkan dengan
Vietnam sekalipun. Bahwa pendidikan menjadi awal tumbuh
kembangnya mereka dari keterpurukan yang terjadi
sebelumnya. Sebaliknya bangsa kita yang terlalu berpikir
industrialized sampai lupa untuk memperkokoh pondasi dari
struktur pembangunan yang namanya pendidikan.
Konseptual Pendidikan di Indonesia Historisme pendidikan bangsa Indonesia adalah hasil
dan pengaruh dari politik etis, dimana pengaruh politik etis
dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan
sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan
dan pengajaran di Hindia Belanda.
Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa
dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925)
yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama
lima tahun (1900-1905).
Sejak tahun1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik
untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata
di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah
terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang
Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung
politik etismerasa prihatin terhadap pribumi yang
mendapatkan diskriminasi sosial-budaya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha
menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari
belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model
Barat,yang mencakup proses emansipasi dan menuntut
pendidikan ke arah swadaya. Wikipedia, Politik Etis. 2014.
101
Melanjutkan apa yang telah dicapai sebelumnya,
pemerintah dengan berbgai regulasi terus berusaha untuk
melindungi serta mengembangkan pendidikan, didalam
pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan
UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal
20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakandan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan
memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang (Rencana
Strategis Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014).
Pendidikan diupayakan berawal dari manusia apa
adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai
kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan
menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia
yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada
lain adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa
kapada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya;
mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar,
berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya.
Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk
mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada
pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman,
moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas
dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan
manusia.
Dalam masyarakat, mau tidak mau pendidikan yang
berkualitas harus dibentuk oleh pemerintah. Pendidikan harus
menjadi ranah yang mudah dijangkau oleh siapapun di
102
republik ini. Omong kosong jika pemerintah bercita-cita
menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara kita, jika
pendidikan masih menjadi second opinion bagi pemerintah
dalam mengeluarkan kebijakan. Membangun negara melalui
pendidikan yang ramah bagi semua tidaklah rugi. Masyarakat
yang akan tercipta adalah masyarakat dengan tahap saling
menghormati tiap hak yang melekat pada diri individu dan
meningginya sikap toleransi (suarakarya-online).
Harapan tentang bagaimana semua orang bisa
merasakan pendidikan, bisa mendapatkan hak pendidikannya
maka seharusnyalah pemerintah sudah memikirkan
pendekatan pendidikan yang merakyat yang nantinya akan
dibahas pada bagian selanjutnya.
Belajar Dari Universitas Di Perancis Pikiran tak pernah muncul dari ruang kosong. Ia
bukanlah hasil creatif yang nihil yang seolah vakum dari
sejarah, dari relasi-relasi sosial, dan sekonyong-konyong
hadir dengan penuh gegap gempita. Pikiran mesti dilihat
sebagai ekspresi dari relasi antar berbagai prakondisi
material: situasi sosial, politik, ekonomi, konfigurasi sejarah
dan akhirnya juga institusi, baik dalam arti formal
(universitas) dan informal (café, salon des artistes).
Pertama-tama kita lihat Universitas Paris atau apa yang
dikenal sebagai Sorbonne. Universitas Paris didirikan pada
tahun 1200 oleh Raja Philippe Auguste dan didukung melalui
dekrit kepausan oleh Paus Gregorius IX pada tahun 1231
yang mencakup empat fakultas: teologi, hukum, kedokteran
sebagai fakultas utama, dan kesenian sebagai fakultas rendah.
Pada tahun 1257, penasihat Raja Louis IX, Robertde Sorbon,
mendirikan fakultas khusus untuk para pelajar teologi yang
miskin kampus inilah yang nantinya dikenal sebagai
Universitas Sorbonne. Oleh karena kampus tersebut
perlahan-lahan meraih posisi politik yang kuat, maka
semenjak abad ke-15 keseluruhan universitas Paris dikenal
sebagai Sorbonne. Pada masa itu, fakultas teologi di
103
Sorbonne memegang peran politik yang kuat dengan hak
untuk menyensor atas nama Raja dan Paus. Kekuatan politik
ini sebegitu efektifnya sampai-sampai seorang filsuf
sekaliber René Descartes, ketika ia menerbitkan bukunya
yang dianggap sebagai tonggak kelahiran filsafat Modern,
Meditasi tentang Filsafat Pertama, merasa perlu untuk „minta
restu‟ dari dekan dan para doktor „fakultas suci Teologi di
Paris‟ dan mempersembahkan karyanya itu kepada mereka
seraya memohon patronase (Suryajaya, 2011).
Di luar „Sorbonne‟ atau Universitas Paris, terdapat
institusi pendidikan lain yang paling bergengsi di kalangan
intelektual filsafat Prancis. Institusi itu tak lain adalah École
Normale Supérieure (ENS). Institusi ini adalah salah satu
dari sederet „Sekolah-Sekolah Besar‟ (Grandes Écoles) yang
muncul dari tradisi Revolusi Prancis (semuanya didirikan
pada masa itu), contoh lain yang cukup terkenal ENS
didirikan pada tahun 1794 di Rue d‟Ulm oleh menteri
pendidikan kala itu, Joseph Lakanal, untuk menempa para
pelajar sebagai pengajar yang betul-betul menguasai
problematika kajiannya sehingga dapat memberikan
pelajaran yang terbaik. Paranormaliens (sebutan bagi para
mahasiswa yang belajar di ENS) tidak memperoleh gelar
akademik apapun dan oleh sebab itu mereka mesti juga
mengambil programsarjana dan pasca-sarjana di kampus lain.
Uniknya, walau tidak menjanjikan gelar apapun, ENS tetap
berdiri sebagai sekolah elit dengan standar yang sangat tinggi
dan dengan deretan panjang para pendaftar. Di antara para
calon mahasiswa yang nantinya menjadi filsuf besar pun,
jumlah yang gagal pada ujian pertama cukup banyak; Derrida
gagal dalam ujian pertamanya, Foucault pun demikian dan
bahkanmesti mengulang kelas persiapan (khâgne) untuk
mengikuti ujian, Lyotard gagal dua kali dalam ujiannya dan
akhirnya memilih masuk Sorbonne.
Minimnya jumlah mahasiswa yang diterima ini
disebabkan oleh standar ujian masuk yang memang sangat
tinggi. Namun penempaan yang keras dalam ENS ini terbukti
104
membuahkan hasil. Ini terlihat dari fakta bahwa tingginya
presentase jumlah para pengajar di Sorbonne yang berasal
dari ENS Institusi ketiga yang layak disoroti di sini adalah
Collège de France yang sudah didirikan sejak tahun 1530
oleh Raja François I. Collège ini berbeda dari kampus pada
umumnya karena selain ia tak menyediakan gelar apapun
bagi yang mengikuti kuliah-kuliahnya dan tidak mengadakan
ujian apapun, kepesertaannya pun Sepenuhnya terbuka dan
bebas biaya. Seluruh masyarakat Prancis boleh datang dan
mengikuti kuliah yang diberikan dalam Collège. Institusi ini
sangat prestisius bagi kalangan intelektual Prancis karena
para anggotanya, yakni pengajar yang diizinkan memberi
kuliah dalam Collège, diangkat secara khusus oleh para
anggota senior dan hanya intelektual yang dipandang telah
benar-benar mencapai puncak penguasaan atas bidangnyalah
yang dipilih menjadi anggota. Alan Schrift mencatat bahwa
peran Collège terutama bersifat kultural, atau dengan kata
lain, non-akademik (Schrift2006: 193). Karena publiknya
tersusun dari seluruh lapisan masyarakat Prancis dengan latar
belakang yang beragam, maka keuntungan menjadi pengajar
di Collège adalah dapat mempengaruhi secara langsung
lanskap kebudayaan Prancis secara umum (Suryajaya, 2011).
Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia Reformasi pendidikan tinggi tidak terlepas dari
tranformasi kekuasan dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai proses pendelegasiaan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, dalam konteksregional dan global, Indonesia menjadi contoh baik terjadinya gerakan transformasi dari sentralisasi kekuasaan menuju desentralisasi khususnya dalam pendidikan.
Pasca tumbangnya orde baru hingga 12 tahun
berikutnya, pemerintah Indonesia berencana memberikan
ruang yang lebih besar kepada universitas berupa otonomi
khususnya keuangan. Hal ini sebelumnya penuh didanai oleh
keuangan negara. Ini arah baru tercermin dalam penerapan
105
beberapa peraturan hukum (PP No 60 dan 61Tahun 1999,
UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Dalam HELTS, otonomi universitas didefinisikan
sebagai desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada
institusi. Sejalan dengan itu, Welch juga menjelaskan bahwa
penerapan Badan Hukum merupakan cermin dari
desentralisasi pendidikan di universitas. PTN mendapatkan
otonomi dalam banyak aspek pengelolaan universitas, namun
mereka juga harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada
pemangku kepentingan. Status otonom harus dijelaskan
sebagai otoritas besar universitas untuk memperbaiki sumber
keuangan, sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas
universitas. Universitas-universitas otonom merupakan
elemen penting dari hasil reformasi pendidikan tinggi. Dalam
sistem terpusat lama, pemerintah pusat telah mendorong
pengembangan kurikulum. Peran pemerintah pusat telah
sangat kuat, bahkan dengan standar nasional yang dirancang
di tingkat pusat. Sistem universitas mengadopsi standar
nasional yang kaku, jika tidak maka tidak bisa diakui oleh
otoritas politik dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Hidayat 2012).
Pengalaman Yang Bisa Dipelajari Membandingkan dua situasi yang berbeda bukanlah
sesuatu yang mudah, mungkin setiap insan pendidikan akan
berharap agar bangsa kita bisa mencontoh apayang telah
terjadi di perancis beberapa waktu yang lalu. Namun
perkembangan pendidikan yang terjadi disana merupakan
bentuk evolusi dari karakter pendidikan yang berawal
tumbuh kembangnya masih didominasi oleh kekuasaan raja
hinga tataran strata pendidikan menemukan identitasnya
sendiri sebagai lembaga yang menghasilkan sumberdaya
manusia yang luar biasa.
Perkembangan pendidikan di Indonesia juga
merupakan warisan dari pola konservatif yang mana pada
masanya hanya kelas tertentu saja yang mampu mengakses
106
pendidikan tersebut. Terlepas dari itu semua, saat ini
pendidikan yang sementara kita dapatkan adalah sebuah
penjewatahan atas apa yang dikonstruksi oleh pemimpin
negara.
Sejarah membuktikan di awal Republik akan dibentuk
hanya kaum feodal yang memiliki kesempatan lebih untuk
mengenyam pendidikan, hingga akhirnya Orde Baru tiba
pendidikan pun masih milik mereka yang bermodal. Coba
kembali kita pahami apa yang terjadi di masa 1600-1700 di
Prancis, kepesertaannya pun sepenuhnya terbuka dan bebas
biaya, seluruh masyarakat Prancis boleh datang dan
mengikuti kuliah yang diberikan dalam Collège. Sekolah
bahkan tidak memberikan gelar kepada mahasiswanya karena
yang dibentuk bukanlah logika formal namun lebihpada
subtansinya ketika seseorang akan memahami apa yang
dipelajarinya. Untuk Indonesia masih memiliki karakter
sentralis yang sangat kuat untuk pengendalian seluruh sistem
pendidikan, kita contohkan saja ketika universitas harus
menerima mahasiswa baru maka yang dipakai adalah ukuran
penilaian kolektif. Aturan dasar SNPTN dijadikan rujukan
kepada seluruh calon mahasiswa yang mengikuti tesmasuk,
artinya ada suatu generalisasi penilaian untuk setiap individu
yang akan mengakses perguruan tinggi negeri. Maka akan
timbul ketidak adilan ketika orang yang selama 12 tahun
belajar di Papua harus bersaing memperebutkan jatah bangku
kuliah dengan orang Jakarta.
Kita bisa bayangkan orang seperti Derrida, Lyotard,
bahkan Foucault harus gagal untuk masuk pada salah satu
universitas di Perancis. Penyebabnya bukan pada ketidak
mampuan akademik namun sistem yang memaksa mereka
untuk memiliki kompetensi, tentang keahlian yang ingin
mereka miliki. Lebih jauh kita lihat apa yang dihasilkan oleh
perguruan tinggi kita? Secara kasat mata bisa kita temui
pertanyaan maupun pernyataan berikut ini; Lalu apa yang
harus saya kerjakan setelah lulus?, Orang tua akan selalu
menanggung beban baik secara lahir dan batin, Nanti lah
107
kalau ada rejeki saya lanjut S2, Tunggu kalo ada peluang
untuk kerja, Entah lah yang jelas saya sudah sarjana!.
Hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalaman
yang terjadi di Prancis, bahwa bangsa kita masih mengukur
pendidikan dengan nominal, kita masih memakai standar
angka untuk menilai kualitas peserta didik maka nilai akan
selalu menjadi momok dan biaya akan menjadi belenggu.
Memakai pola dari teori aktif, pandangan yang menekankan
pengamatan input pendidikan secara kolektif. Di mana sudut
terpenting yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah
proses kematangan pribadi para siswa yang harus difasilitasi,
dia komodasi kebutuhannya dan dibimbing menuju
kedewasaan. Oleh karena itu, proporsi organisasi sekolah
yang cenderung mekanistis harus dipola menjadi fleksibel
agar para anggotanya bisa berekspresi dengan optimal
(Ravik, 2008).
KESIMPULAN Pada bagian terakhir, ada beberapa perihal yang bisa
saya simpulkan, bahwasanya dengan model pendidikan yang
masih mendahulukan populis ketimbang subtansi maka kita
akan selalu berada pada tataran pragmatis. Ada beberapa
usulan yang kiranya bisa kita diskusikan bersama terkait
pendidikan dan kajian politik adalah; sudah waktunya
Kementrian Pendidikan berdiri sendiri tanpa harus ikut pada
cabinet yang sedang berjalan, ini untuk memutus mata rantai
dominasi dari penguasa terhadap kebijakan pendidikan.
Kedua, adanya regulasi pendidikan yang mengisyaratkan
bahwa pendidikan itu asasi dan diberikan hukuman bagi yang
melanggar, serta adanya jaminan untuk mendapatkan hak
pendidikan bagi setia prakyat. Ada modulasi pajak khusus
yang diarahkan hanya untuk pendidikan, jadi untuk biaya
pendidikan tidak akan dipolitisasi oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan terakhir yaitu mensikronkan antara arah
pembangunan pendidikan dengan sumber daya pendidikan.
108
DAFTAR PUSTAKA
Adian, Donny Gahral. 2006. Percik Pemikiran Kontemporer :
Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta. Jalasutra.
Ariyanto, Teguh. 2003. Kondomisasi di Indonesia perspektif
hukum islam. UIN Sunan Kalijaga.
Aunullah, Indi. 2006.Bahasa Dan Kuasa Simbolik Dalam
Pandangan Pierre Bourdieu. Fakultas Filsafat.
Universitas Gadjah Mada.
Baker, Anita. Kompasiana.com
Bartholomew, Craig. 2001. “Christ and Consumerism: An
Introduction” dalam Christ and Consumerism: A Critical
Analysis of the Spirit of the Age (ed. Craig Bartholomew
danThorsten Moritz; Cumbria: Paternoster,).
Baudrillard, Jean. 2013. Masyarakat Konsumsi. Yogyakarta.
Kreasi Wacana.
Bauman, Zygmant. 2005. Work, Konsumerism And The New
Poor. Second Edition. Open University Press.
Best, Steven dan Douglas Kellner. 1991. Postmodern Theory:
critical Interrogations. New York. The Guilford Press.
BKKBN. 2003. Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria
Kondom. Jakarta.
www.Changingminds.org
Cohen, B.j. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rineka
Cipta.
Damani, Muhammad. 2002. Makna Agama Dalam Masyarakat
Jawa. Yogyakarta. LESFI.
Featherstone, Mike. 2008. Postmodernisme Dan Budaya
Konsumen. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Firovani, Adikila. 2013. Konsumerisme: Konsumsi Demi
Prestise. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
Harker, Richard. 2005. (Habitus x Modal) + Ranah.
Yogyakarta. Jalasutra.
Hidayat, Rakhmat. 2012. Politik Pendidikan Tinggi Indonesia
Pasca Orde Baru: Reformasi Tata Kelola Dalam
109
Perspektif New Public Management. Jurnal Komunitas
Volume 6 Nomor 2.
Ignatius, Bambang Sugiharto. 2013. Arah dan Kecenderungan
Filsafat Barat Masa Kini: Sebuah Sketsa.
Ismail, Dr Arifudin. 2012. Agama Nelayan, Pegumulan Islam
dan Budaya Lokal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Jenkins, Richard. 1992. Pierre Bourdieu. New York. Routledge.
Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta.
PT. Rineka Cipta.
Lash, Scott. 2013. Sosiologi Post Modernism. Yogyakarta.
Kanisius.
Lebow, Victor. 2009. Wordpress.Com
Lechte, John. 2001. 50 Filsuf Kontemporer: Dari
Strukturalisme sampai Postmodernitas. Yogyakarta.
Kanisius.
Lyotard, Jean Francois. 1984. The Postmodern Condition : a
Report on Knowledge. Manchester.
M. Francis Abraham. 1991. Modernisasi Di Dunia Ketiga.
Yogyakarta. PT Tiara Wacana.
Martono, Nanang. 2012. Kekerasan Simbolik di Sekolah;
Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu.
Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
McLuhan, Marshall. 1964. Understanding Media: Extension of
Man. New York: MIT Press.
Nasikun, DR. 1991. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta. CV
Rajawali.
Noor, Irfan M. Hum. 2013. Realitas Agama dan Problem Studi
Ilmiah-Empiris (Kajian Filsafat Ilmu atas Pemikiran
Peter L. Berger).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 61
Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai
Badan Hukum.
Piliang,Yasraf Amir. 2004. Dunia yang dilipat : Tamasya
Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Bandung Jalasutra.
110
----------. 2009. Posrealitas. Yogyakarta. Jalasutra.
Polanyi, Karl. 2003.Transformasi Besar. Yogyakarta. Pustaka
Pelajar.
Purbo W. Onno , 2003. Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber.
Jakarta. Penerbit Republika.
Radea.web.id. 2008.
Ravik.staff.uns.ac.id. 2008.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi
Modern. Jakarta : Prenada Media
Ritzer, George. 2003. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta.
Kreasi Wacana.
--------------. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik
Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
--------------. 2013. Teori Sosiologi. Yogyakarta. Kreasi Wacana
Ryadi, Agustinus. 2013. Postmodernisme Versus Modernisme.
Malang. STFT Widya Sasana.
Saefudin A.M. et al. 1991. Desekularisasi Pemikiran, Landasan
Islamisasi. Bandung. Mizan.
Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, 1990. Sosiologi Pedesaan Jilid 2.
Gajah Mada University Press.
Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial; Sketsa teori dan refleksi
metodologi kasus Indonesia. Yogyakarta. PT Tiara
Wacana.
Samekto. 2005. Kapitalisme Modernisasi dan Kerusakan
Lingkungan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Steuerman, Emilia, 2000. The Bounds of Reason: Habermas,
Lyotard and Melanie Klein on Rationality. Routledge.
Suryajaya, Martin. 2011. Sistem Pendidikan dan Pemikiran
Filsafat Prancis Kontemporer. Jurnal Kajian Wilayah.
Vol. 2, No. 2.
Tarmiji, Ahmad. 2014. Meretas Jalan Sosiologi Pendidikan Ibnu
Khaldun: Antara Pendidikan Karakter dan Pendidikan
Nasionalisme. Komunitas.
111
Tilaar, H.A.R. 2012. Perubahan Sosial dan Pendidikan
Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia.
Jakarta. Rineka Cipta.
Tjondronegoro, Sediono M.P. 1998. Keping-keping Sosiologi
Dari Pedesaan. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Trentman, Frank. 2004. “Beyond Consumerism: New Historical
Perspectiveson Consumption”, Journal of contemporary
History, vol. 39, No. 3, Jul.
Wattimena, Reza A.A. 2012. Berpikir Kritis bersama Pierre
Bourdieu.
Widiyanto, 2010, Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan.
Surakarta. LPP dan UPT Universitas Sebelas Maret.
Wikipedia.org. 2014. Jean François Lyotard.
wikipedia.org. 2014. Kondom.
Wikipedia.org. 2014. Politik Etis.
www.Kompas.com
www.Muslim.or.id
Wirawan, Prof. DR. I. B. 2012. Teori-teori Sosial Dalam Tiga
Paradigma. Jakarta. Kencana.
Wiryomartono, Bagoes P. 2001. Pijar-pijar Penyingkap Rasa :
Sebuah Wacana Seni dan Keindahan dari Plato sampai
Derrida. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
www.arrahmah.com. 2012.
www.sikondom.com. 2013.
www.suarakarya-online.com.
Yusuf, Akhyar. 2003. “Matinya narasi besar, berkembangnya
narasi kecil dan permainan kebenaran dalam perspektif
posmodernisme”: Pusat Pengembangan Penelitian FIB
Universitas Indonesia.
--------2003. Bahasa, Pertarungan Simbolik dan kekuasaan.
Basis. Edisi 11-12.
0
Biografi Penulis
Chairul Basrun Umanailo, Lahir di Ambon 22 Nopember 1978. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah Umum di Kota Ambon, kemudian menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Sosiologi Universitas Sebelas Maret pada 2002. Bekerja dan berkarier sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas
Iqra Buru masih dijalani dan saat ini, penulis masih menyelesaikan studi S2-Sosiologi di Universitas Sebelas Maret. Aktifitas sehari-hari dijalani dengan kegiatan penelitian, diskusi maupun workshop dan seminar, Prestasi akademik yang di raih pada akhir 2014 yaitu Finalis Essay penulisan terbaik Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang diadakan oleh HMP Universitas Gajah Mada dan Juara 1 Resensi Buku Pierre Bourdieu; Menyikap Kuasa Simbolik yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Penulis juga masih merampungkan beberapa hasil karya yang akan diterbitkan; Eksistensi Petani Indonesia, Sosiologi Hukum, dan Perspektif Masyarakat Buru dalam Kajian Kontemporer. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail; [email protected] dan 0852-4302-5000.
Tri Yatno, Lahir di Wonogiri 24 Oktober 1980 menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah Umum di Kota Wonogiri, kemudian menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Buddha pada STABN Raden Wijaya Wonogiri. Bekerja dan berkarier sebagai pengajar di STABN Raden Wijaya Wonogiri masih dijalani dan saat ini, penulis masih menyelesaikan studi S2-
Sosiologi di Universitas Sebelas Maret. Penulis dapat dihubungi
melalui E-mail; [email protected] dan 087736348469.