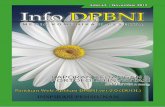PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN...
i
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DAN PENDAPATAN DOMESTIKREGIONAL BRUTO (PDRB)
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah
Tahun 2010-2012)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu PersyaratanMemperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Disusun Oleh :
Siti Aisyah31401204620
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Siti Aisyah
NIM : 31401204620
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi UNISSULA Semarang
menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja
Modal” dan diajukan untuk di uji pada tanggal:
12 September 2014
Adalah hasil karya saya
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau
sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara
menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat
atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau
pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah olah
sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat
bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau
yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa
memberikan pengakuan penulis aslinya.
Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila
terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau
meniru tulisan orang lain yang seolah-olah tulisan saya
sendiri. Dan saya bersedia bila gelar dan ijasah yang
diberikan universitas dibatalkan.
Semarang, 12 September
2014
Yang membuat pernyataan,
Siti Aisyah31401204620
HALAMAN MOTO
Dalam kerendahan hati ada ketinggian budiDalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwaDalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu
Hidup memerlukan pengorbananPengorbanan memerlukan perjuanganPerjuangan memerlukan ketabahanKetabahan memerlukan keyakinanKeyakinan menentukan kejayaanKejayaan menentukan kebahagiaan
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (darisesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS(Al-'Asyr) 94:5-8)
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnyaAllah menyukai orang-orang yang bertawakal(kepada-Nya)” (QS Ali ‘Imraan:159).
Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuakutercinta, semoga aku selalu berbakti kepadanya menjadi
anak yang soleha, amien...
ABSTRAK
Pelaksanaan desentralisasi fiskal selainmemberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah jugamempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhikepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuanuntuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik
Regional Bruto terhadap Alokasi Belanja Modal diProvinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2012.Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.Selanjutnya dalam penelitian ini, hanya berfokusmeneliti data keuangan Provinsi Jawa Tengah periodetahun 2010- 2012. Metode analisis dalam penelitian inimenggunakan uji regresi yang dilakukan dengan mengujiefek dari variabel independen ke variabel dependen.Analisis yang digunakan dalam penelitian adalahanalisis kuantitatif. Dengan mengunakan alat analisiskuantitatif yaitu uji asumsi klasik dan uji regresilinier berganda. Berdasarkan pengujian dan pembahasanyang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujianuji asumsi klasik, yang terdiri dari ujimultikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, ujiautokorelasi dan uji normalitas ternyata semua variabelbebas berpengaruh positif dan signifikan terhadapBelanja Modal. Sedangkan hasil pengujian regresi linierberganda yang terdiri dari Dana Alokasi Umum,DanaAlokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan ProdukDomestik Regional Bruto yang merupakan variabel bebassecara simultan atau (uji F) berpengaruh positif dansignifikan terhadap anggaran Belanja Modal di ProvinsiJawa Tengah. Dan secara parsial atau (uji t)menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum danPendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif dansignifikan terhadap anggaran Belanja Modal sedangkanProduk Domestik Regional Bruto dan Dana Alokasi Khusustidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran BelanjaModal.
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus,Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Brutodan Belanja Modal.
ABSTRACT
The implementation of fiscal decentralization inaddition to give authority to local governments alsoinfluence the ability of regions to meet the publicinterest. The aim of this study is to examine theinfluence of General allocation fund, specialallocation fund, regional own revenue, brutto regionaldomestic product to the Capital Budget Appropriation inCentral Java Province in 2010-2012. This research wasfield study research. The analysis used in the researchwas quantitative analysis. The quantitative analysistools were classic assumption test and multiple linearregression test. Based on the examination anddiscussion, it could be concluded that the classicalassumption test, which consists of multikoliniarititytest, heteroscedasticity, autocorrelation test and thetest of normality test which is all independentvariable positive and significant impact on thecapital expenditure budget. While the results ofmultiple linear regression test consisting of GeneralAllocation Fund, Special Allocation Fund, Regional ownRevenue and Brutto Regional Domestic Product which is
simultaneous or independent variable (F test) and asignificant positive effect on capital expenditurebudget in the province of Central Java. And partiallyor (t test) showed that only the General AllocationFund and the Local Revenue had positive and significantimpact on the budget, while Capital Expenditure BruttoRegional Domestic Product and the Special AllocationFund had no significant effect on the capitalexpenditure budget.
Keywords: General allocation fund, special allocation fund, regionalown revenue, brutto regional domestic product, and capital expenditur
KATA PENGANTAR
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal”.
Penulisan Skipsi ini telah melibatkan banyak
pihak yang tentunya dengan sepenuh hati telah
meluangkan waktu dan dengan penuh keikhlasan memberi
informasi yang dibutuhkan. Adapun pihak-pihak yang
telah ikut membantu dalam proses penulisan Skripsi ini
adalah:
1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Rustam Hanafi ,SE.,M.Sc., Akt, CA selaku Ketua
Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Hendri Setyawan ,SE,MPA selaku dosen
pembimbing selaku pembimbing yang senantiasa
membimbing materi dalam proses penyusunan Skripsi
ini.
4. Bapak, Ibu, kakak, adik dan sahabat terima kasih
atas doa, dukungan dan semangatnya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.
Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.
Semarang, 12 September
2014
Peneliti
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI....................... ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.................. iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....................... iv
HALAMAN MOTO...................................... v
ABSTRAKSI......................................... vi
KATA PENGANTAR....................................viii
DAFTAR ISI........................................ ix
DAFTAR TABEL......................................xiii
DAFTAR GAMBAR..................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN................................... xv
Halaman
BAB I PENDAHULUAN................................ 1
1.1 Latar Belakang.......................... 1
1.2 Rumusan Masalah......................... 9
1.3 Tujuan Penelitian....................... 10
1.4 Manfaat Penelitian...................... 11
BAB IITINJAUAN PUSTAKA........................... 12
2.1 Landasan Teori.......................... 12
2.1.1 Teori Keagenan..................... 12
2.1.2 Desentralisasi Fiskal di Indonesia. 14
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) 16
2.1.4 Dana Alokasi Umum.................... 19
2.1.5 Dana Alokasi Khusus................. 22
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah............ 24
2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto............... 28
2.1.8 Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 31
2.2 Penelitian
Terdahulu .............................................
..................................................32
2.3 Hubungan Logis Antara Variabel dan Perumusan
Hipotesis 33
2.3.1 Hubungan Antara DAU terhadap
Pengalokasian Anggaran ...........................
Belanja................................. 34
2.3.2 Hubungan Antara DAK terhadap Pengalokasian
Anggaran
Belanja................................. 35
2.3.3 Hubungan Antara PAD terhadap
Pengalokasian Anggaran ...........................
Belanja................................. 36
2.3.4 Hubungan Antara PDRB terhadap
Pengalokasian Anggaran ...........................
Belanja................................. 37
2.4 Kerangka Pemikiran...................... 39
BAB III
METODE PENELITIAN.......................... 40
3.1 Jenis Penelitian ....................... 40
3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel
40
3.2.1 Variabel Dependen (Y): Pengalokasian
Anggaran Belanja ..........................
Modal................................... 40
3.2.2 Variabel Independen (X).............. 41
3.2.3.1 DAU (Dana Alokasi Umum)............ 41
3.2.3.2 DAK (Dana Alokasi Khusus).......... 41
3.2.3.3 PAD (PendapatanAsli Daerah)........ 42
3.2.3.4 PDRB (Pendapatan Domestik Regional
Bruto) 43
3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.. 43
3.4 Jenis dan Sumber data................... 44
3.5 Metode Pengumpulan Data................. 44
3.6 Metoda Analisis Data.................... 44
3.6.1 Statistik Deskriptif............... 45
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik............ 46
3.6.2.1 Uji Normalitas..................... 46
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas.............. 46
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas............ 47
3.6.2.4 Uji Autokorelasi................... 48
3.6.3 Pengujian Hipotesis................. 48
3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R2).......... 49
3.6.3.2 Uji Simultan......................
49
3.6.3.3 Uji t (Uji Parsial)............... 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............ 51
4.1 Deskripsi Sampel ....................... 51
4.2 Statistik Deskriptif.................... 51
4.3 Analisis Data...........................
54
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.................. 54
4.3.1.1 Uji Normalitas..................... 54
4.3.1.2 Uji Multikolonieritas.............. 55
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas............ 56
4.3.1.4 Uji Autokorelasi................... 57
4.3.2 Pengujian Hipotesis................ 58
4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R2)......... 58
4.3.2.2 Uji Simultan (Uji F)............... 59
4.3.2.3 Uji t (Uji Parsial)................ 60
4.4 Pembahasan ............................. 62
BAB V PENUTUP..................................... 68
5.1
Kesimpulan.............................................
..................................................68
5.2 Keterbatasan ...........................
69
5.3 Saran .............................
69
5.4 Implikasi ............................. 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 ............................................Penelitian Sebelumnya
33
TABEL 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian Jawa Tengah
2010-2012 ............................................52
TABEL 4.2 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov ..........
55
TABEL 4.3 Uji Multikolonieritas....................
56
TABEL 4.4 Uji Heteroskedastisitas.....................
57
TABEL 4.5 Uji Autokorelasi Model Regresi..............
58
TABEL 4.6 Koefisien Determinasi.......................
59
TABEL 4.7 Uji Model F.................................
59
TABEL 4.8 ............................................Uji Model t
60
Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010
Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2011
Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012
PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 s/d 2012
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun 2010
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun 2011
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun 2012
Hasil Regresi Linier
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hubungan perimbangan antara pemerintah dan daerah,
menjadi kunci pokok keberhasilan pelaksanaan otonomi
daerah, karena daerah memerlukan sumber-sumber keuangan
guna membiayai belanja daerah. Semenjak dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang
Pemerintahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 (direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004) tentang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang
tersebut memisahkan fungsi Pemerintahaan Daerah
(Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi
tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan
eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim
& Abdullah, 2006). Peraturan perundang-undangan
tersebut secara implisit merupakan bentuk kontrak
antara eksekutif, legislatif, dan publik di dalam
pemerintahan.
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang
dijadikan dasar dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen
anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kota
dan kabupaten. APBD mempunyai peranan penting bagi
pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi
dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi
pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintahaan Daerah baik
dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran
yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008).
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 proses
penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu
eksekutif (Pemerintahaan Daerah) dan legislatif (DPRD),
dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia
anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana
operasionalisasi daerah yang mempunyai kewajiban
membuat draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif
bertugas mengesahkan rancangan APBD dalam proses
ratifikasi anggaran.
Penyusunan anggaran daerah diawali dengan membuat
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan anggaran belanja. Dalam pembuatan
rancangan APBD yang sesuai dengan kebijakan umum APBD,
Prioritas dan Plafon Anggaran pihak eksekutif
menyerahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan
dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai
Peraturan Daerah. Dalam prespektif keagenan, hal
tersebut merupakan bentuk kontrak (incomplete
contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk
mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto
dan Yustikasari, 2007).
Desentralisasi fiskal yang dimiliki pemerintah
daerah memberikan kewenangan yang besar kepada daerah
tersebut untuk menggali potensi yang ada sebagai sumber
pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah
dalam rangka pelayanan publik. Dalam penjelasan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan
daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat
diperbaiki dengan melakukan perbaikan manajemen
kualitas jasa (service quality management), yaitu upaya
meminimalisi kesenjangan (gap) antara tingkat
layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2010).
Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu
mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik
karena belanja modal merupakan salah satu langkah
bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan
kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007)
menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja
seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif,
misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah
daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program
layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan
bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk
kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat
meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu
diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap
pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus.
Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintahaan Daerah,
Pemerintahaan Pusat akan mentransfer dana perimbangan
yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil pada pemerintah daerah
untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan desentralisasi
fiskal. Dengan adanya dana transfer dari Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan
roda pemerintahan secara efektif dan efisien dalam
meningkatan pelayanan publik.
Kemampuan keuangan yang tidak sama di masing-
masing daerah dalam mendanai kegiatannya, menimbulkan
ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah
lainnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dalam
mengatasi ketimpangan fiskal tersebut yaitu dengan
pemerintah memberikan alokasi dana yang bersumber dari
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari
pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang
pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan penyelenggaran urusan
pemerintahaan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
Dengan adanya transfer dana dari pusat tersebut
diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan
PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di
daerahnya.
Pemerintahaan Pusat memberi pendelegasian wewenang
kepada Pemerintahan Daerah disertai dengan pengalihan
dana, sarana dan prasana serta Sumber Daya Manusia
(SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana
perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana
Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang
telah ditetapkan. Pemanfaatan DAK diarahkan pada
kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan,
dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur
ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan
adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi
belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset
tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan
pelayanan publik.
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu
tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola
sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan
baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan
ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Salah
satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi
ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan
pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi
perbaikan kesejahteraan. Namun yang terjadi peningkatan
pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan
peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat
dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan
dengan total anggaran belanja daerah.
Dalam pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran
belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan
kepentingan-kepentingan politis. Anggaran yang
sebenarnya bertujuan memenuhi kebutuhan publik terhadap
sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Namun, dengan adanya kepentingan
politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam
penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja
modal terdistorsi dan menjadi tidak efektif dalam
mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat (Keefer
dan Khemani, 2003 dalam Halim 2004).
Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk
aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan
diharapkan mampu menciptakan produktivitas perekonomian
di masyarakat, karena semakin tinggi belanja modal
semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.
Seharusnya pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik melakukan perubahan komposisi
belanja, karena selama ini belanja daerah lebih banyak
digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang
produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan
belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang
produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan
pelayanan publik. Sejalan dengan pendapat tersebut,
Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007)
menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih
banyak untuk program–program pelayanan publik. Kedua
hasil penelitian diatas ini menyiratkan pentingnya
pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan
publik.
Fenomena praktik dalam penyusunan anggaran, usulan
yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan
mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi,
1998 dalam Darwanto dan Yustikasari 2007). Eksekutif
mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agency-nya,
baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara
Darwanto dan Yustikasari (2007) maupun Putro (2010),
menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh
legislatif untuk memenuhi self-interestnya. Hal ini
berarti banyak anggaran belanja daerah tidak digunakan
untuk belanja modal melainkan untuk belanja yang
lainnya.
Menurut rilis Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA) dalam www.seknasfitra.ord (diakses
Februari 2014) menunjukkan bahwa beban belanja pegawai
pada APBN memang semakin berat. Pada RAPBN 2012,
belanja pegawai merupakan alokasi belanja tertinggi,
sebesar Rp. 215,7 triliun. Bahkan mengalahkan belanja
subsidi yang selama ini mendominasi. Potret yang sama
terjadi di daerah. Hasil analisa FITRA pada APBD 2011,
terdapat 124 daerah yang beban belanja pegawainya
melebihi 60% dan 16 daerah diantaranya mencapai 70%.
Analisis Kemenkeu juga menunjukan, belanja pegawai
terbesar di Kabupaten Demak dengan mencapai 89%.
Di Jawa Tengah komposisi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Jateng 2013 juga dinilai tidak
ideal, sebab perbandingan antara alokasi belanja tidak
langsung dengan belanja langsung memiliki perbedaan
yang tinggi, yakni 73,43 % dan 26,57 % . Sebelumnya
atau pada tahun 2012, perbandingan belanja tidak
langsung dibandingkan belanja langsung ialah 60% dan
40% (www.suaramerdeka.com, akses Januari 2014).
Belanja tidak langsung di antaranya untuk belanja
pegawai sedangkan belanja langsung meliputi berbagai
kebutuhan pembelanjaan sarana prasarana masyarakat
seperti perbaikan jalan dan jembatan. Semakin besarnya
anggaran belanja tidak langsung ini menjadikan
masyarakat kurang bisa merasakan dampak APBD secara
optimal.
Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di
mana belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi
anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah
daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena
kurangnya dana untuk membiayai pembangunan
infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam
anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga
mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dari latar belakang diatas menjelaskan bahwa
pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan
publik sangatlah penting maka dari pemanfaatan belanja
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif seperti
aktivitas pembangunan. Hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007)
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli
daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan
terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa
variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal, namun pendapatan domestik regional
bruto tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan
Sugiartiana (2012) yang memperoleh hasil bahwa pada
variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempunyai korelasi
yang tinggi terhadap variabel independen lainnya, maka
variabel tersebut harus dihapuskan/dihilangkan, pada
variabel pendapatan asli daerah memiliki hasil bahwa
variabel PAD tidak berpengaruh positif terhadap belanja
modal dan pada variabel dana alokasi umum memperoleh
hasil bahwa DAU berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil
penelitian terdahulu tersebut menggambarkan bahwa
adanya kontradiksi hasil yang berbeda yang telah
dilakukan, untuk itu perlu dilakukan penelitian kembali
terhadap variabel tersebut.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Sugiartiana
(2012) yaitu untuk membuktikan pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal.
Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam
penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen
yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini
dilakukan pada lingkup lokasi yang lebih luas yaitu
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan
periode penelitian 2010-2012, karena dengan menggunakan
data tiga tahun terakhir dari penyusunan penelitian
diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan
untuk kondisi belanja modal saat ini.
1.2 Rumusan Masalah
Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia
memakai system terpusat, dimana segala sesuatu
diputuskan dan ditentukan oleh pemerintah pusat, dengan
demikian daerah-daerah wajib patuh dan tunduk pada
pemerintah pusat, oleh karena itu perkembangan daerah
sangat tidak merata. Sedangkan pada masa Reformasi
bergulir, dijalankan sistem otonomi daerah dimana
daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dengan
batasan-batasan tertentu.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana
pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah
pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah
berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai
pembangunan pemerintah daerah, disamping hal itu
Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana
sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
membantu pembiayaan pada Belanja Daerah.
Berdasarkan pada perbedaan hasil penelitian
sebelumnya (Darwanto dan Yustikasari (2007) , Tuasikal
(2008) dan Sugiartiana (2012) , serta keterbatasan yang
ditemui dalam penelitian sebelumnya, maka pertanyaan
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
terhadap anggaran belanja modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh
terhadap anggaran belanja modal ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh
terhadap anggaran belanja modal ?
4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap anggaran belanja
modal ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi
Khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh PDRB terhadap
anggaran belanja modal
1.4 Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan
manfaat diantaranya :
1. Bagi Pemerintahan Daerah, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya
mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi
kemajuan daerah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumber
referensi dan informasi untuk memungkinkan
penelitian selanjutnya tentang topik ini.
3. Bagi akademik memberikan sumbangan terhadap ilmu
pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran.
Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan
bagi penelitian-penelitian lainnya yang tertarik
pada bidang kajian ini.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan
keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di
antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen,
dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen
untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal
(Jensen dan Meckling, 1976 dalam McCue dan Prier).
Hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan
yang dilakukan seseorang mempunyai pengaruh kepada yang
lain yaitu ketika seseorang sangat bergantung pada
tindakan orang lain, dimana ketergantungan tersebut
diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur
institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma
perilaku dan konsep kontrak.
Hubungan antara eksekutif/birokrasi dengan
legislatif/kongres dinyatakan sebagai self-interest model
(Johnson, 1994). Dalam hubungan tersebut pihak
legislatif ingin dipilih kembali, birokrat ingin
memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin
memaksimumkan utilitasnya. Oleh karena itu agar
legislator terpilih kembali, mereka mencari cara dalam
program dan projects yang mereka buat supaya mereka
menjadi poluler di mata konstituennya. Sebagai birokrat
dalam rangka mengembangkan agency-nya, mereka
mengusulkan program-program yang bisa mendatangkan
benefit untuk pemerintah. Dalam hal tersebut apabila
semua pihak dapat bertemu dalam kepentingan yang sama,
maka konsensus di antara legislator dan birokrat
merupakan keniscayaan, bukan pengecualian.
Scott (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan
bahwa teori keagenan merupakan cabang dari game
theory yang mempelajari suatu model kontraktual
dimana mendorong agen untuk bertindak bagi
prinsipal saat kepentingan agen bisa saja
bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal
pendelegasian pertanggungjawaban atas pengambilan
keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung
jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja
atas persetujuan bersama.
Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan
prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah
karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan
pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki,
manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan
dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan
prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan
informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga
timbul adanya asimetri informasi (asymmetric
information). Mursalim (2005) dalam Bangun (2009)
menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak
dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan
tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan
kepentingan untuk memaksimalkan utiliti (self-
interest). Sedangkan bagi prinsipal akan sulit
untuk mengontrol secara efektif tindakan yang
dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit
informasi yang ada.
2.1.2.Desentralisasi Fiskal di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan
desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk
menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,
sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan
lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi
bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman
yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi
masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.
Desentralisasi yang terfokus pada tingkat kabupaten
dan kota berada pada level ketiga setelah pemerintah
pusat dan provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa
desentralisasi harus dilaksanakan pada tingkat provinsi
karena provinsi dianggap lebih memiliki kapasitas yang
besar untuk menangani seluruh tanggung jawab yang
dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun
demikian, sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa
pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara
politis jika harus membentuk pemerintahan otonom
provinsi yang kuat.
Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang
berskala kabupaten/kota meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pendidikan;
g. Penanggulangan masalah sosial;
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan pertanahan;
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
Pada hakikatnya, terdapat tiga prinsip dalam
implementasi otonomi daerah di Indonesia (Sri Rahayu,
2010), yaitu:
1. Desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota
sehingga otonomi lebih dititik beratkan pada daerah
tersebut.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pembentukan pemerintahan di daerah pada prinsipnya
adalah untuk lebih memberdayakan peran serta pemerintah
dan masyarakat di daerah dalam pembangunan wilayah.
Mardiasmo (2004:59) menyatakan bahwa tujuan utama
penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan
perekonomian daerah.
Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16
tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa:
1. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran
Belanja, dan Pembiayaan.
3. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli
Daerah.
4. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi,
dan jenis belanja.
Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 Pasal 1
ayat 1 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2009 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 Pasal 22 ayat 1, struktur APBD merupakan satu
kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Halim (2007) menyatakan bahwa APBD merupakan
rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam
bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu
(satu tahun) serta merupakan salah satu instrument
utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum
dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran daerah
digunakan sebagai alat untuk menentukan besar
pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi
pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber
pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi
kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat
koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit
kerja.
Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan
tanggung jawab Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pada Undang-
Undang Nomor 17 pasal 6 Tahun 2003 presiden selaku
kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Kekuasaan itu antara lain: diserahkan
kepada Bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Penganggaran memerlukan kerjasama para
pimpinan satuan kerja dalam organisasi pemerintahan.
Struktur organisasi satuan kerja menunjukkan tanggung
jawab setiap pelaksana anggaran. Setiap pelaksana
bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola elemen
anggarannya masing - masing.
Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku
Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan. Laporan keuangan
tersebut harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah yang menyusun laporan keuangan
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan
daerah. Laporan Keuangan tersebut oleh PPKD disampaikan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya
laporan keuangan pemerintah daerah ini disampaikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Penyusunan APBD merupakan kegiatan pertama dan
utama dalam proses anggaran. Proses penyususnan
anggaran dimulai dari eksekutif dalam hal ini Bappeda,
Dinas Keuangan dan BPKD. Biro Keuangan serta institusi
yang terkait dalam perencanaan pembuatan draf/
rancangan oleh suatu komite atau panitia yang kemudian
akan diserahkan kepada legislatif untuk dibahas dan
disepakati bersama pemerintah. Dalam perspektif
keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete
contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk
mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal
(capital expenditure) merupakan sebuah proses yang sarat
dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran yang
diberikan pemerintah daerah secara cuma-cuma
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana
dan prasarana umum. Namun, adanya kepentingan politik
dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses
penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal
terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan
permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003
dalam Putro, 2010). Dalam konteks pengelolaan keuangan
daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan
perencanaan keuangan jangka panjang, terutama
pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang
dihasilkan dari belanja modal tersebut. Hal ini berarti
bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan
kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan
pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan
aset tersebut.
2.1.4. Dana Alokasi Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana
Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu alat
bagi pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan di Indonesia dengan tujuan mengurangi
ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan
pajak antara Pusat dan Daerah, yang telah diatasi
dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan
Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal
sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri).
Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU
akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh
sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini
sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen
Keuangan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh
suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan
dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap, di mana
kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan
daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity).
Dengan begitu DAU dapat digunakan untuk menutup
celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi
dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan
konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-
daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih
kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai
kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU
yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah,
khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat
memperoleh DAU yang negatif.
Dalam pengaturan keuangan menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer
antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang
disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus. Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang
bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua
kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan
antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan
didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-
pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa
daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih
banyak dari pada daerah yang kaya. Dengan kata lain
tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan
kemampuan penyediaan pelayanan publik antar Pemerintah
Daerah di Indonesia (Kuncoro, 2004).
DAU yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN
dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin
dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi
dan 90% untuk Kabupaten / Kota.
Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah dalam mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antar daerah melalui penetapan
formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi
daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya
celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan
daerah dan potensi daerah. Dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan kembali mengenai
formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU.
Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar
tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi
DAU relatif kecil begitu pula sebaliknya. Secara
implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU
sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
2.1.5.Dana Alokasi Khusus
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website
www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan :
1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan
kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional,
dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana
dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang
telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan
prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil,
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah
tertinggal/ terpencil, daerah rawan
banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah
ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan
kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi
terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus
di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta
infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap
pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui
kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta
mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan
mengurangi risiko bencana melalui kegiatan
khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat
penyediaan serta meningkatkan cakupan dan
kehandalan pelayanan sarana dan prasarana dasar
dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui
kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang
terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten,
kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di
bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi
kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan
yang didanai dari anggaran Kementerian/ Lembaga dan
kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan yang digunakan untuk
mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan
daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari
anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen
Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.
Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan
perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur
ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana
fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK
diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran
belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah
aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan
pelayanan publik.
2.1.6.Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal
1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber
penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang
digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan
yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari
pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang
yang diterima dari masyarakat/sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri selama tahun takwim (kalender), guna
membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik
pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk
biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan
bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah.
1. Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah,
yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pembangunan
Daerah.
Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur
dengan peraturan pemerintah dan penetapannya
seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah
Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan
daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang
pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan
sumber pendapatan asli daerah sebagaimana diatas,
terlihat bahwa sumber pendapatan daerah berupa pajak
daerah sangat bervariasi.
2. Retribusi Daerah
Di samping pajak daerah, sumber pendapatan
asli daerah yang cukup besar peranannya dalam
menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli
daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah
merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang
dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung
atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah (Pemda) oleh kepentingan orang pribadi atau
badan.
Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa
dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat
langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan,
karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di
mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar
dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar
tertentu oleh si pembayar retribusi. Tarif
retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan
retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau
mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.
Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di
suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi
yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan
iuran retribusi itu dianut asas manfaat (benefit
principles). Dalam asas ini besarnya pungutan
ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh
si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya
adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang
diterima oleh orang yang membayar retribusi
tersebut dan menentukan berapa besar pungutan
yang di pungut.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Milik Daerah Yang Dipisahkan
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan
Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran
penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah
adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.
Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka
menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan
ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara
yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil
pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik
daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan
Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak,
retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, antara lain
hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro
Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah
ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses
pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya
proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding
besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Indikator
desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan
total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak
daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba
bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan
lain –lain.
2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto
Proses pembangunan mencakup perubahan pada
komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan
(alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor
kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi
kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan
pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan
dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output
perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perkapita. Boediono (dalam Putro, 2010)
menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian
indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun
waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh,
lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi
akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang
ada di dalam perekonomian itu sendiri.
Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi
adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total
nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara
atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai
barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau
lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang
paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh
performa dari suatu perekonomian.
Blakely (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari
(2007) mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah,
dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi
pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah
sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal,
kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi
sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi
perekonomian internasional, kapasitas pemerintah
daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan
pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan
semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu
akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta
maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah
lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.
Menurut pandangan tokoh ekonom klasik (Adam Smith,
David Ricardo, Thomas Robert Malthis, dan John Stuart
Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert M.Solow, J.R
Hicks, Irving Fisher dan Gossen), pada dasarnya ada
empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang
modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat
teknologi yang digunakan (Sanusi, 2004). Suatu
perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih
tinggi dibanding apa yang dicapai pada masa sebelumnya.
Menurut Boediono (1985) dalam Prathama dan Mandala
(2005), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan
output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses
mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis.
Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini,
masih terus menyempurnakan makna, hakikat, dan konsep
petumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan
pertambahan PBD dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot
yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan,
kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan
masyarakat luas (Arsyad, 1999).
PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan
oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam
praktiknya adalah dengan membagi-bagi perekonomian
menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin).
Jumlah output masing -masing sektor merupakan jumlah
output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada
kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor
perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa
juga merupakan input bagi sektor ekonomi juga atau lain
lagi.
Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan
terjadi perhitungan ganda (double counting) atau bahkan
multiple counting. Akibatnya PDB bisa menggelembung
beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk
menghindarkan hal diatas maka dalam perhitungan PDB
dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai
tambah ( value added ) masing-masing sektor.
Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara
nilai output dengan nilai input antara .
Dimana :
NT = Nilai Tambah
NO = Nilai Output
NI = Nilai Input antara
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah
jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor
perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai
tambah bruto adalah nilai produk (output) dikurangi 1
(satu) dengan biaya antara. Nilai tambah bruto
NT= NO-NI
mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan
gaji) bunga sewa, tanah dan keuntungan. Dengan
menghitung nilai tambah tersebut dapat diketahui jumlah
PDRB nya.
2.1.8.Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada
masyarakat, setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun
prioritas belanja modal dan perencanaan yang baik
sehingga dapat menjadi kunci untuk menyiasati kendala
yang dihadapi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah
aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih
dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang
sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,
serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah
merupakan akibat adanya belanja modal menjadi syarat
utama dalam memberikan pelayanan publik. Dalam
meningkatkan kuantitas aset tetap, pemerintah daerah
mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam APBD, yang setiap tahunnya Pemda selalu
melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas
anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan
dampak jangka panjang secara finansial.
Kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki dengan
melakukan perbaikan manajemen kualitas jasa (service
quality management), yaitu upaya meminimalisi
kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan
harapan konsumen (Bastian, 2010). Dengan demikian,
Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan
anggaran belanja modal dengan baik karena belanja
modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah
Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
Dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dapat
dilihat dari optimalisasi penerimaan PAD yang hendaknya
didukung dengan upaya Pemerintah Daerah dengan
meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD
yang berlebihan justru akan semakin membebani
masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan
mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo dalam
Tuasikal, 2008).
Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja
modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal,
seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
Khusus (DAK}
2.2 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
NO Peneliti danTahun Variabel
HASIL
1 Syukriy Abdullahdan Abdul Halim (2004)
Dana AlokasiUmum
Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadapBelanja Pemerintah Daerah
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadapBelanja Pemerintah Daerah
Belanja Pemerintah Daerah
2Yulia Yustikasari dan Darwanto (2007)
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomiberpengaruh signifikan terhadapBelanja Modal
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadapBelanja Modal
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Belanja Modal
3 Iin Indarti Sugiartana (2012)
PertumbuhanEkonomi (PDRB)
Pertumbuhan Ekonomi(PDRB) mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel independenmaka variabel tersebut dihapuskan/dihilangkan
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positifterhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum berpengaruh positiftetapi tidak signifikan terhadapBelanja Modal Belanja Modal
NO Peneliti danTahun Variabel HASIL
4 Askam Tuasikal (2008)
Dana AlokasiUmum
Dana Alokasi Umum berpengaruh positifterhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khususberpengaruh positifterhadap Belanja Modal
Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
Produk DomestikRegional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Belanja Modal
2.3 Hubungan Logis Antara Variabel dan Perumusan
Hipotesis
2.3.1 Hubungan Antara DAU Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
Dana perimbangan keuangan merupakan
konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian,
terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat menggunakan dana
perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan
pelayanan kepada publik yang direalisasikan
melalui belanja modal (Solikin, 2010). Hasil
penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007)
menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan
signifikan antara DAU dengan belanja modal.
Penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin
memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan
bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik,
bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu
ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer
pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal
ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa
perilaku belanja daerah khususnya belanja modal
akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.
Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan
semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal
juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah
yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi
untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan
meningkat. Untuk itu hipotesis pertama yang dihasilkan
adalah sebagai berikut:
H1 : DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
2.3.2 Hubungan Antara DAK Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.
Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi
Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah
untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK
untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang
harus ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana
dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur
ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan
DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan
dalam belanja modal. Selain itu ada yang berpendapat
bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu
sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara
pemberian dana transfer dari pemerintah pusat
(DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah
melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori
dan hasil penelitian sebelumnya tersebut maka
menghasilkan hipotesis sebagai berikut:
H2 : DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
2.3.3 Hubungan Antara PAD Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan
kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat
dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam
menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar
pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin
besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam
melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi
daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik
dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara
untuk meningkatkan pelayanan publik dengan
melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang
direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).
Menurut Mardiasmo (2004), Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah. Belanja Modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim,
2004).
Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
alokasi belanja modal. Temuan ini dapat
mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah
satu faktor penentu dalam menentukan belanja
modal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan
pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja
modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah
dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.
Sehingga apabila Pemerintah Daerah ingin
meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah
harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan
landasan teori dan beberapa hasil penelitian
diatas maka hipotesis berikutnya adalah sebagai
berikut :
H3 : PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasianAnggaran Belanja Modal
2.3.4 Hubungan Antara PDRB Terhadap PengalokasianAnggaran Belanja ModalKebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang
diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong
pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah
yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan
ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat
berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan
pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah
dengan daerah lainnya (Putro, 2010).
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan
output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik
Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk
peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut
penelitian Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto (2007)
bahwa upaya desentralisasi memberikan pengaruh
yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Oates (1995) dalam Lin dan Liu (2000) dalam
Darwanto (2007) membuktikan bahwa antara desentralisasi
dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang
positif dan signifikan. Darwanto (2007) menyatakan
bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain
sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal,
kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi
sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi
perekonomian internasional, kapasitas pemerintah
daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan
pembangunan.
Berdasarkan landasan teori dan argumen di
atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan
otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi
masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan
potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi
tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan
mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta
maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan
pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran
belanja modal. Oleh karena itu, untuk hipotesis untuk
variabel ini dinyatakan sebagai berikut:
H4: PDRB berpengaruh positif terhadap pengalokasianAnggaran Belanja Modal
2.4 Kerangka Pemikiran
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
DAU
DAK
PAD
PDRB
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini
adalah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran
belanja modal. Gambar 2.1 menyajikan kerangka
pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada
penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada
penelitian yang dilakukan Iin Indarti Sugiartiana
(2012) dengan variabel penelitian yaitu variabel
independen pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
untuk variabel tambahan. Sedangkan variabel
dependen yang digunakan adalah variabel belanja modal.
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
(+)
(+)
(+)
(+)
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu
fenomena empiris yang disertai data statistik,
karakteristik dan pola hubungan antar variabel.
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel
Menurut Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang
dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen
merupakan variabel yang menjadi perhatian utama
peneliti sedangkan variabel independen merupakan
variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik
secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Dalam
penelitian ini terdapat satu variabel Dependen dan
empat variabel Independen, varibel tersebut antara
lain :
3.2.1 Variabel Dependen (Y) : Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
Menurut Peratutan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, belanja modal adalah belanja langsung yang
digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset
tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan
aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal
dapat diukur dengan:
3.2.2 Variabel Independen (X)
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri
dari:
3.2.2.1 DAU (Dana Alokasi Umum)
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja
Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan
Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan
Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
Adalah transfer yang bersifat umum dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk
mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
Dana Alokasi Umum untuk masing-masing
Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos
dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.
Variabel dana alokasi umum (DAU) dapat diukur
dengan:
Dimana :
AD : Gaji PNS Daerah
CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
3.2.2.2 DAK (Dana Alokasi Khusus)
Dana Alokasi Khusus merupakan dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang
DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Alokasi DAK setiap daerah
ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
Dalam penghitungan alokasi DAK dilakukan
melalui 2 (dua) tahapan yaitu:
a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
dan
b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing
daerah
Dalam penentuan daerah tertentu harus memenuhi
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria
teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing
daerah ditentukan dengan perhitungan indeks
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan
kriteria teknis (Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2012).
3.2.2.3 PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan daerah asli yang
digali di daerah tersebut untuk digunakan
sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah
untuk memperkecil ketergantungan dana dari
pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah
terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli
daerah diukur dengan rumus :
PAD = Pajak Daerah + Retribusi
Daerah + Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan +
3.2.2.4 PDRB (Pendapatan Domestik Regional
Bruto)
PDRB Nominal (atau disebut PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDRB tanpa
memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDRB
riil (atau disebut PDRB Atas Dasar Harga
Konstan) mengoreksi angka PDRB nominal dengan
memasukkan pengaruh dari harga. PDRB dapat
dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu
pendekatan pengeluaran dan pendekatan
pendapatan. Rumus umum untuk PDRB dengan
pendekatan pengeluaran adalah:
3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dari
tahun 2010-2012. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten
PDRB = konsumsi + investasi + pengeluaran
pemerintah + ekspor - impor
dan kota di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini
menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode
dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota
yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang
digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa
Tengah yaitu 35 kabupaten / kota.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Sumber data dari
dokumen laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota
Povinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Biro Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari laporan
realisasi APBD tahun 2010-2012 dapat diperoleh
data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per
kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Jawa Tengah
3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam mengumpulan data
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari
sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat,
dan mengolah data yang berkaitan dengan data.
3.6 Metode Analisis Data
Metode analisis data merupakan metode yang
digunakan untuk mengolah dan memprediksi hasil
penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.
Berdasarkan judul, latar belakang, dan perumusan
masalah maka teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda yang
bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)
linear antara dua variabel atau lebih. Adapun model
yang digunakan dari regresi linear berganda yaitu:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e
Dimana:
Yt-1 = Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal (PABM)
X1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X4 = Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
β0 = Konstanta
β1-4 = Parameter/koefisien regresi
variabel independen
e = variabel pengganggu
3.6.1Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata
(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan
distribusi). (Ghozali, 2011).
3.6.2Pengujian Asumsi Klasik
3.6.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel dependen dan variabel
independen mempunyai distribusi normal atau tidak.
Model regresi yang baik, memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi
normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik.
Test statistik yang digunakan untuk menguji normalitas
adalah dengan metode statistik uji Kolmogorov Smirnov test
(K-S) yang nilai signifikansinya >0,05 maka disimpulkan
data terdistribusi normal. (Ghozali, 2011). Uji K-S
dilakukan dengan membuat hipotesis:
H0 = Data residual terdistribusi normal
Ha = Data residual tidak terdistribusi normal
Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S
adalah sebagai berikut:
a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan
secara statistik maka H0 ditolak, yang berarti
data terdistibusi tidak normal.
b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak
signifikan statistik maka H0 diterima, yang
berarti data terdistibusi normal.
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali (2011), uji ini digunakan untuk
mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variable
bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Jika terdapat korelasi antara variabel independen,
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel
ortogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas
dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value
atau variance inflation factor (VIF). Sebagai dasar acuannya
dapat disimpulkan:
1. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas
antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka
dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar
variabel independen dalam model regresi.
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain(Ghozali, 2011).
Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas
dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi
adanya heteroskedastisitas perlu adanya pengujian untuk
mendeteksi apakah ada heteroskedastisitas, salah
satunya dengan uji Glesjer. Dasar pengambilan keputusan
uji heteroskedastisitas melalui uji Glesjer dilakukan
sebagai berikut.
1. Apabila probabilitas nilai test dari persamaan
regresi signifikan statistik, yang berarti data
empiris yang diestimasi terdapat
heteroskedastisitas.
2. Apabila probabilitas nilai test tidak signifikan
statistik, maka berarti data empiris yang diestimasi
tidak terdapat heteroskedastisitas.
3.6.2.4 Uji Autokolerasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas
dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya
dijumpai pada data deret waktu (time series). Konsekuensi
adanya autokorelasi dalam model regresi adalah variance
sample tidak dapat menggambarkan variance populasinya,
sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat
digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada
nilai independen tertentu (Ghozali, 2011).Untuk
mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini, dapat
dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW
test).
3.6.3Pengujian Hipotesis
Setelah melakukan pengujian normalitas dan
pengujian atas asumsi- asumsi klasik, langkah
selanjutnya yaitu melakukan pengujian atas hipotesis 1
(H1) sampai dengan hipotesis 4 (H4). Pengujian tingkat
penting (Test of significance) ini merupakan suatu prosedur
dimana hasil sampel digunakan untuk menguji kebenaran
suatu hipotesis (Ghozali, 2011) dengan alat analisis
yaitu uji t, uji F dan nilai koefisien determinansi
(R2). Perhitungan statistik disebut signifikan secara
statistik, apabila uji nilai statistiknya berada
dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak).
Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila uji nilai
statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.
3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen, terbatas. Sebaliknya,
nilai R2 yang mendekati satu menandakan variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali,
2011). Nilai yang digunakan adalah adjusted R2 karena
variabel independen yang digunakan dalam penelitian
ini lebih dari dua buah.
3.6.3.2 Uji Simultan ( Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji apakah semua
variabel independen yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen (Ghozali, 2011). Untuk menguji
hipotesis yang digunakan dalam uji F dapat dilihat
dari kriteria sebagai berikut:
1. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05
(α=0,05)
2. Membandingkan F hitung dengan F tabel
a. Bila F hitung < F tabel, variabel independen
secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen.
b. Bila F hitung > F tabel, variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel
dependen.
3.6.3.3 Uji t (Uji Parsial)
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi
pengaruh varibel independen terhadap variabel dependen
secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2011). Oleh karena itu uji t ini
digunakan untuk menguji hipotesis Ha1, Ha2, Ha3, dan
Ha4 Langkah–langkah pengujian yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Quick look: jika jumlah degree of freedom (df) adalah
20 atau lebih, derajat kepercayaan sebesar 5%
atau kurang dari 0,05 , maka H0 yang menyatakan
bi=0 dapat ditolak bila t lebih besar dari 2
(dalam nilai absolut).
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik
kritis menurut tabel. Jika nilai statistik t hasil
perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t
tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa suatu variabel independen secara individual
mempengaruhi variabel dependen diterima.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Sampel
Data sampel penelitian ini adalah data yang
diambil dari pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-
Jawa Tengah antara lain Laporan Realisasi APBD, data
Produk Domestik Regional Bruto, data Pendapatan Asli
Daerah, dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang
diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Jawa Tengah dan
melalui situs internet departemen keuangan dengan
alamat http://www.djpk.depkeu.go.id/ dan juga dari Biro
Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 35
pemerintah kabupaten dan kota selama tahun 2010 sampai
dengan tahun 2012. Atas dasar penentuan jumlah sampel
yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka
diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama 2010
sampai dengan 2012 adalah sebesar 35 pemerintah
kabupaten dan kota selama 3 tahun penelitian maka
diperoleh sebanyak 3 x 35 = 105 data pengamatan.
4.2. Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk
mengetahui sebaran nilai dari variabel-variabel
penelitian. Hal –hal yang akan dikaji dalam membahas
analisis deskriptif adakah nilai rata-rata, nilai
maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel.
Berikut adalah hasil output perhitungan deskriptif
statistik menggunakan SPSS 20.
Tabel 4.1
Deskripsi Variabel Penelitian Jawa Tengah 2010-2012
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PDRB 105 1849275.56 54384654.53 11080003.5810 10373521.89615DAU 105 238069009000
.001057808013000.
00609261702657.1
427182759525680.20
050DAK 105 17730100000.
00118901780000.0
062540325238.09
5221815177524.384
35PAD 105 42395561052.
00667883642000.0
0103233547637.5
14377791039182.452
62BM 105 55247479000.
00549227727415.0
0184078436037.3
04887807605732.406
33Valid N (listwise) 105
Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran
Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa dari
N sampel sebanyak 105, di mana nilai rata-rata variabel
PDRB yang diperoleh dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah selama tahun 2010-2012 menunjukkan rata-rata
sebesar Rp 11.080.003,58 per tahun, dengan perolehan
nilai maksimum sebesar Rp 54.384.654,53 dan nilai
minimumnya sebesar Rp 1.849.275,56 dengan standar
deviasi Rp 10.373.521,89 dari rata-rata. Dengan melihat
angka laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada suatu daerah
maka dapat memberikan gambaran bagaimana pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah
tersebut.
Pada variabel DAU diperoleh keterangan nilai rata-
ratanya sebesar Rp 609.261.702.657,14 per tahun, dengan
nilai maksimum sebesar Rp 1.057.808.013.000,00 dan
nilai minimumnya sebesar Rp 238.069.009.000,00 dengan
standar deviasi Rp 182.759.525.680,20 dari rata-rata.
Dana Alokasi Umum (DAU) berperan penting dalam
mewujudkan pemerataan keuangan antar daerah dalam
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Pada variabel DAK diperoleh keterangan nilai rata-
rata sebesar Rp 62.540.325.238.09 per tahun, dengan
perolehan nilai maksimum sebesar Rp 118.901.780.000,00
dan nilai minimumnya sebesar Rp17.730.100.000,00 dengan
standar deviasi Rp 21.815.177.524,38 dari rata-rata.
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN
dialokasikan kepada daerah agar berfungsi dalam
membiayai kebutuhan tertentu untuk menutup kesenjangan
publik antar daerah dengan memberi prioritas
pendidikan, pertanian prasarana pemerintahan daerah dan
lingkungan hidup.
Pada variabel PAD diperoleh keterangan nilai rata-
rata sebesar Rp 103.233.547.637,51 per tahun, dengan
perolehan nilai maksimum sebesar Rp 667.883.642.000,00
dan nilai minimumnya sebesar Rp 42.395.561.052,00
dengan standar deviasi Rp 77.791.039.182,45 dari rata-
rata. PAD merupakan pendapatan daerah yang
menggambarkan kemampuan daerahnya dalam merealisasikan
PAD yang direncanakan guna membiayai pengeluaran daerah
pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah.
Secara keseluruhan PAD Provinsi Jawa Tengah mengalami
kenaikan, peningkatan PAD ini merupakan akibat
perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah.
Pada variable BM diperoleh keterangan nilai rata-
rata sebesar Rp 184.078.436.037,30 per tahun, nilai
maksimum sebesar Rp549.227.727.415,00 dan nilai
minimumnya sebesar Rp 55.247.479.000,00 dengan standar
deviasi Rp 87.807.605.732,40 dari rata-rata. Belanja
modal mempunyai pengaruh yang begitu penting dalam
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya
ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,
karena alokasi belanja modal adalah alokasi dana yang
mendukung dalam penyediaan dan pembangunan
infrastruktur publik.
4.3. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi linier berganda. Untuk analisis tersebut
maka terlebih dahulu diuji untuk tidak adanya masalah
penyimpangan terhadap asumsi klasik.
4.3.1. Uji Asumsi Klasik
4.3.1.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel-variabel independen dan
variabel dependen mempunyai distribusi normal atau
tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan
dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan
adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian
diperoleh dalam tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov TestUnstandardized Residual
N 105Normal Parametersa Mean .0000089
Std. Deviation 4.85838939E10
Most Extreme Differences
Absolute .067Positive .067Negative -.052
Kolmogorov-Smirnov Z .687Asymp. Sig. (2-tailed) .732a. Test distribution is Normal.
Berdasarkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.687
dan signifikansi pada 0.732 hal ini berarti H0 diterima
yang berarti data residual terdistribusi normal.
4.3.1.2. Uji Multikolinieritas
Pengujian terhadap gejala multikolinearitas ini
dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat
korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel
independen dalam model persamaan regresi. Adanya
multikolinearitas dalam model persamaan regresi yang
digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi,
sehingga mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis
nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi
tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif
terhadap perubahan data. Pengujian multikolinieritas
dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel
penelitian tolerance dan VIF. Hasil pengujian
multikolinieritas adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
CollinearityStatistics
BStd.Error Beta
Tolerance VIF
1 (Constant)
-2.747E10 1.720E10 -1.597 .114
PDRB 388.551 692.480 .046 .561 .576 .457 2.186DAU .250 .051 .521 4.887 .000 .270 3.708DAK .090 .388 .022 .232 .817 .329 3.036PAD .477 .091 .422 5.253 .000 .474 2.111
a. Dependent Variable: BM
Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran
Pengujian multikolinierits menggunakan nilai VIF
menunjukkan bahwa nilai VIF semuanya lebih kecil dari
10 dan nilai tolerance meununjukkan lebih dari 0,10,
sehingga persamaan yang terjadi dinyatakan bebas dari
multikolinieritas.
4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas
Asumsi Heteroskedastisitas menguji apakah dalam
sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka
disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda disebut
heteroskedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan Uji
Glesjer. Asumsi utama Uji Glesjer yaitu dengan
melakukan regresi variabel independen terhadap
residual. Adapun hasil pengujian dengan Uji Glesjer
terdapat pada Tabel 4.4 berikut:
Tabel 4.4Uji Heteroskedastisitas Glesjer
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant
) 3.477E10 1.012E10 3.437 .001
PDRB -576.202 407.261 -.202 -1.415 .160DAU .049 .030 .305 1.637 .105DAK -.241 .228 -.178 -1.056 .294PAD -.048 .053 -.127 -.903 .369
a. Dependent Variable: Abs_res
Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran
Hasil tampilan output SPSS dengan jelas
menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai
sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel
dependen abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada
tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05
atau 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak
mengandung adanya heterokedastisitas.
4.3.1.4. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali uji autokorelasi bertujuan
menguji apakah dalam model regresi linear terdapat
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi digunakan uji
Durbin Watson.. Jika antar residual tidak terdapat
hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak
atau random. Berikut ini hasil uji autokorelasi dalam
model regresi:
Tabel 4.5Uji Autokorelasi Model Regresi
Model Summaryb
Model R R SquareAdjusted RSquare
Std. Errorof theEstimate
Durbin-Watson
1 .833a .694 .682 4.95460E10 1.907
a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, PDRB, DAUb. Dependent Variable: BM
Sumber: Data sekunder yang diolah, tahun 2013
Hasil uji Durbin watson menunjukkan nilai DW
dipeorleh sebesar 1,907 yang berada diantara du = 1,77
dan 4 – du = 2,23. Dengan demikian nilai DW berada
diantara du dan 4 – du. Dengan demikian model regresi
tidak memiliki masalah autokorelasi.
4.3.2. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan
menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi
berganda bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara
dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah
hubungan antara variabel dependen dengan independen.
Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan
uji koefisien determinasi (R2), uji F (uji simultan)
dan uji t (uji parsial).
4.3.2.1. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menunjukkan besarnya
pengaruh variabel bebas yaitu PDRB, DAU, DAK dan PAD
secara bersama–sama terhadap belanja modal.
Tabel 4.6Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R SquareAdjusted RSquare
Std. Errorof theEstimate
1 .833a .694 .682 4.95460E10a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, PDRB, DAU
Nilai koefisien determinasi disajikan pada Tabel
4.8 sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat kita
ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R
Square) adalah sebesar 0,682 atau 68,2%. Hal ini
berarti bahwa variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK secara
bersama – sama memiliki pengaruh sebesar 68,2% terhadap
alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan sisanya
sebesar 0,318 atau 31.8 % dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut.
4.3.2.2. Uji Simultan (Uji F)
Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F
yaitu menguji pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK
secara bersama–sama terhadap alokasi anggaran untuk
belanja modal.
Tabel 4.7Uji Model
ANOVAb
ModelSum ofSquares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 5.564E23 4 1.391E23 56.662 .000a
Residual 2.455E23 100 2.455E21Total 8.019E23 104
a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, PDRB, DAUb. Dependent Variable: BM
Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7
sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui
bahwa F hitung (156,662) dengan signifikansi sebesar
0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh dari PDRB, DAU, DAK dan PAD secara bersama–
sama terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.
4.3.2.3. Uji t (Uji Parsial)
Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh
variabel-variabel bebas secara parsial terhadap
variabel terikatnya. Berikut adalah hasil perhitungan
nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam
penelitian ini:
Tabel 4.8
Uji Model t
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) -2.747E10 1.720E10 -1.597 .114
PDRB 388.551 692.480 .046 .561 .576DAU .250 .051 .521 4.887 .000DAK .090 .388 .022 .232 .817PAD .477 .091 .422 5.253 .000
a. Dependent Variable: BM
Model persaman regresi diperoleh sebagai
berikut:
Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada tabel
4.8 hasil pengujian hipotesis diperoleh sebagai
berikut:
1. Hipotesis 1.1: Dari hasil estimasi koefisien
variabel PDRB diperoleh sebesar t = +0,561 dengan
signifikansi sebesar 0.576. Nilai signifikansi yang
lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa PDRB tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja
Modal (BM) satu tahun ke depan.
BM= -2,747E10 + 388,551PDRB + 0,250DAU + 0,090DAK +
2. Hipotesis 2.1: Dari hasil estimasi koefisien
variabel DAU diperoleh sebesar t = +4.887 dengan
signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang
lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa perubahan
DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Belanja Modal (BM) satu tahun ke depan. Arah
koefisien regresi bertanda positif memiliki arti
bahwa peningkatan DAU pada suatu periode justru
akan meningkatkan Belanja Modal (BM) pada satu
tahun ke depan.
3. Hipotesis 3.1: Dari hasil estimasi koefisien
variabel DAK diperoleh t sebesar +0,232 dengan
signifikansi sebesar 0.817. Nilai signifikansi yang
lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa DAK tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja
Modal (BM) satu tahun ke depan.
4. Hipotesis 4.1: Dari hasil estimasi koefisien
variabel PAD diperoleh t sebesar +5.253 dengan
signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang
lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa PAD
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja
Modal (BM) satu tahun ke depan.
4.4. Pembahasan
1. Pengaruh PDRB terhadap Alokasi Anggaran Belanja
Modal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
Alokasi anggaran Belanja Modal pada pemerintah
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa
daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB yang tinggi
tidak selalu mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi.
Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang
memiliki PDRB yang rendah belum tentu mengalokasikan
Belanja Modal yang rendah. Hasil penelitian ini
konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Iin Indarti
Sugiartiana (2012), Askam Tuasikal (2008) dan Darwanto
dan Yustikasari (2007) yang menyatakan pertumbuhan
ekonomi tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang
signifikan. Ini bukan berarti bahwa dalam manajemen
pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan
alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama
dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal,
tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang
mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan
umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain
memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga
kondisi sosial politik di daerah.
Desentalisasi yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dimaksudkan untuk memberikan dampak yang sangat
berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi daerah. Dengan
desentralisasi fiskal yang diundangkan, maka daerah
dengan PDRB yang besar akan memiliki keleluasaan untuk
mengalokasikan dan menentukan sendiri kebutuhan untuk
daerah tersebut.
PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi adalah proses
kenaikan output per kapita. Umumnya Pertumbuhan
Ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan
Produk Domestik Regional Daerah (PDRB). Dengan demikian
daerah dengan PDRB yang tinggi dalam satu periode
menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki banyak
aktivitas yang menunjang pendapatan daerah seperti
misalnya di sektor industri maupun jasa serta pelayanan
publik. Namun demikian infrastruktur yang ada dalam
menunjang pertumbuhan juga akan mengalami kerusakan.
Hanya pada Daerah yang berorientasi pada kelanjutan
untuk mendapatkan PDRB yang tinggi akan
mempertimbangkan untuk selalu menjaga dan memelihara
serta meningkatkan infrastruktur daerahnya sedangkan
beberapa daerah nampaknya kurang mampu menunjang
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan
pertimbangan tersebut maka hanya beberapa daerah yang
mengalokasikan anggaran belanja yang lebih besar untuk
Belanja Modalnya sedangkan beberapa daerah kurang
mendukung hal tersebut.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi
Anggaran Belanja Modal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi
Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
alokasi anggaran Belanja Modal pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa
daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Perimbangan
yang tinggi akan mengalokasikan belanja modal yang
tinggi pula, demikian pula sebaliknya. Daerah
Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Perimbangan yang
rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
Hal tersebut diatas sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007)
dimana variabel DAU memiliki korelasi yang positif,
signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti Sugiartiana
(2012) variabel DAU berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap alokasi belanja modal. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008)
bahwa pengaruh DAU berpengaruh positif terhadap belanja
modal, menunjukkan alokasi belanja modal pemerintah
daerah kabupaten/kota sangat bergantung pada besar
kecilnya alokasi dana perimbangan yang diberikan
pemerintah pusat kepada daerah dalam mewujudkan
pembangunan di daerahnya.
Dana Perimbangan berasal dari pemerintah pusat
berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana
bagi hasil yang berasal dari APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer
yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah
secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah
dipergunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang
tidak penting.
Semakin besar Dana Perimbangan berupa Dana
Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka
kontrol terhadap penggunaan dan alokasi dana tersebut
juga akan semakin besar dilakukan selain kontrol dari
pemerintah daerah juga dilakukan pula control dari
pemerintah pusat. Adanya kontrol yang semakin besar
tersebut menjadikan penggunaan dana perimbangan juga
akan semakin besar untuk dialokasikan dalam mewujudkan
pelayanan umum dan perbaikan serta peningkatan
infrastruktur daerah.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi
Anggaran Belanja Modal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi
Khusus tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa
daerah Kabupaten/Kota yang memiliki DAK yang tinggi ada
yang tidak mengalokasikan belanja modal yang tinggi
pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota
yang memiliki DAK yang rendah tidak selalu
mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
Penelitian ini bertolak belakang pada penelitian
yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) dimana secara
parsial hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAK
berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal,
menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut kemandirian
pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya
terutama untuk belanja modal masih bergantung pada dana
transfer dari pusat.
Dana Perimbangan berupa DAK berasal dari
pemerintah pusat yang bersumber dari APBN kemudian
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Meskipun demikian
nampaknya ada beberapa kendala yang menghambat alokasi
DAK tersebut pada belanja modal sehingga tidak seluruh
DAK dijadikan sumber pembiayaan dalam alokasi belanja
modal.
4. Pengaruh PAD terhadap Alokasi anggaran Belanja
Modal
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi
anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah
Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan
mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian
pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki
PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang
rendah.
Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dan
Askam Tuasikal (2008) dengan hasil PAD berpengaruh
positif terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti Sugiartiana
(2012) memperoleh hasil variabel PAD tidak berpengaruh
positif terhadap alokasi belanja modal, karena potensi
daerah yang kurang maksimal.
Desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan
kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah otonom
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan
kemampuan sendiri berdasar aspirasi masyarakat seperti
yang telah tercantum pada Undang-Undang No 32 Tahun
2004. Di sisi lain kemampuan daerah untuk menyediakan
pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung
pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut
menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu
menciptakan alokasi dana untuk pembangunan daerah yang
berkelanjutan.
Di sisi lain, wilayah dengan sumber dana PAD yang
tinggi dapat memiliki tuntutan yang besar dari
masyarakatnya untuk semakin dapat memperoleh akses yang
besar terhadap pendapatan daerah tersebut. Masyarakat
akan semakin banyak yang menyuarakan pada tuntutan
perbaikan pelayanan umum. Kondisi demikian dapat
mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menyikapinya
sebagai sebuah tuntutan atas pengembalian pendapatan
daerah kepada masyarakat sehingga alokasi Belanja Modal
semakin besar.
BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PDRB
terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa
Tengah.
2. Terdapat pengaruh positif pada Dana Alokasi Umum
terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah Jawa
Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di
bawah 0,05. Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan
Dana Alokasi Umum yang tinggi akan mengalokasikan
Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula
sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan
Dana Alokasi Umum yang rendah akan mengalokasikan
Belanja Modal yang rendah.
3. Tidak terdapat pengaruh positif Dana Alokasi
Khusus terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal Daerah
Jawa Tengah.
4. Terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah
(PAD) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal daerah
Jawa Tengah. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD
yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang
tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah
Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan
mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
1.2 Keterbatasan
Penelitian memiliki keterbatasan yaitu terdapat
perbedaan yang besar pada beberapa data karena berasal
dari pengamatan wilayah yang berbeda. Untuk itu
analisis selanjutnya dapat menggunakan metode Analisis
regresi panel (panel least square atau pool least square)
dengan manambahkan aspek fixed effect yang berasal dari
masing-masing wilayah dan sekaligus dapat mengetahui
wilayah mana yang memiliki pengaruh yang paling besar.
1.3 Saran
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis
model penelitian dengan menggunakan metode panel
atau untuk menunjukkan fixed effect yang diperoleh dari
perbedaaan kondisi PAD, dana perimbangan,
pertumbuhan ekonomi maupun belanja modal yang
terjadi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah
model penelitian dengan menambahkan variabel
seperti halnya variabel non keuangan. Variabel non
keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat
menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat
pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan
pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam
mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
1.4 Implikasi
Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat:
1. Mengalokasikan Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Dana
Perimbangan (DAU dan DAK), dan Pendapatan Asli
Daerah untuk anggaran Belanja Modal yang
diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk
menambah penerimaan daerah sehingga tercipta
kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan
pada pemerintah pusat dapat dikurangi.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari.(2006). “Hubungan Antara PertumbuhanEkonomi Daerah, Belanja Pembangunan danPendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten danKota se Jawa-Bali)“. Simposium NasionalAkuntansi XI, 1 – 26.
Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan DanPembangunan Ekonomi Daerah. BPFE Yogyakarta.
Bangun, Ricky Andra Levy (2009). ”Pengaruh Dana AlokasiKhusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan AsliDaerah Terhadap Pendapatan Perkapita”. Tesis,Universitas Sumatera Utara.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik : SuatuPengantar, Jakarta : Erlangga.
Belajar Melek Anggaran ke SeknasFITRA.www.seknasfitra.org.akses Februari 2014
Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate denganProgram SPSS : Cetakan IV, Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang .
Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. (2004). “PengaruhDana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli DaerahTerhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten danKota di Jawa dan Bali”. Jurnal Ekonomi STEINo.2/Tahun XIII/25.
Halim, Abdul.(2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi KeuanganDaerah, Jakarta Edisi Revisi: Salemba Empat.
Harianto, dan Priyo Hari Adi .(2006). “Hubungan antaraDana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli
Daerah, dan Pendapatan Perkapita”. Skripsi.Saltiga: Fakultas Ekonomi Kristen Satya Wacana.
Johnson, Cathy Marie. 1994. The Dynamics of Conflictbetween Bureaucrats and Legislators. Armonk, NewYork: M.E. Sharpe.
Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008,Akuntansi Sektor Publik : Buku1, Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, Semarang.
Komposisi APBD di Jateng2013.www.suaramerdeka.com.akses Januari 2014.
Kuncoro, Mudrajad. Ph. D. (2004). "Reformasi, Perencanaan,Strategi dan Peluang“. Otonomi dan PembangunanDaerah” : Penerbit Erlangga.
Mardiasmo .(2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: Andi.
McCue, Cliff., Prier, Eric. Using Agency Theory toModel Cooperative Public Purchasing.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akutansi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DanaAlokasi Khusus Tahun Anggaran 2013
Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang PedomanPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2009
Putro, Suratno Nugroho. (2010). “Pengaruh PertumbuhanEkonomi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi
Umum Tehadap Pengalokasian Anggaran BelanjanModal (study kasus pada kabupaten/kota diprovinsi Jawa Tengah)”.Jakarta. UniversitasDiponegoro Semarang.
Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. ” SuatuPengantar“. Teori Ekonomi Makro : Penerbit FE UI.
Sanusi, Bachrawi. (2004). Tokoh Pemikir Dalam MazhabEkonomi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal danKeuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: GhaliaIndonesia.
Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.Jakarta: Salemba Empat.
Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, &Bambang Brodjonegoro. (2002). Dana Alokasi Umum –Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah.Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Solikin, Ikin. 2007, Hubungan Pendapatan Asli Daerahdan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal diJawa Barat, http://file.upi.edu/Direktori.
Sri Rahayu, Ani. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal.Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiartiana, Iin Indarti. (2012). “Pengaruh PertumbuhanEkonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap PengalokasianAnggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode2005-2009”.Jurnal Fokus Ekonomi, Stie PelitaNusantara Semarang.
Tuasikal, Askam (2008). “Pengaruh DAU, DAK, PAD, DANPDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia” Jurnal Telaah danRiset Akuntansi, Universitas Pattimura Ambon.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 tentangKeuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Tentang PemerintahDaerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerahsebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah,Retribusi Daerah.
www.depkeu.djpk.go.id
Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. “PengaruhPertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, danDana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian AnggaranBelanja Modal“. Simposium Nasional Akuntansi X,1 – 25.