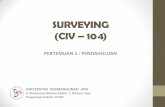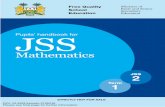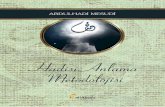pembacaan hadis-hadis nabi dari manaqib rosul “nalal - UIN ...
PENGANTAR STUDI ILMU HADIS - Zenodo
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PENGANTAR STUDI ILMU HADIS - Zenodo
Modul Ulumul Hadis
PENGANTAR STUDI ILMU HADIS
Triansyah Fisa, M.TH
BUKU PERTAMA:Studi Pengantar Hadis Hingga Identifikasi Hadis Daif
BUKU KEDUA:Hadis Maudhu’ Hingga Praktek Takhrij Hadis
Kementerian Agama RISekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Pengantar
Alḥamdu lillāhi Rabil-‘ālamīn, Allah swt. yang selalu memandang hambanya denganpenuh kasih sayang, Rab yang selalu membimbing hambanya menuju pintu keridaanNya.Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. yang selalu menjadi suritauladan bagi umatnya dalam menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
Modul ini di upayakan dapat membimbing mahasiswa dalam mempelajari ilmu-ilmuhadis dalam memahami hadis Nabi, karena Ulumul hadis merupakan salah satu matakuliahwajib bagi mahasiswa dalam menempuh studi di perguruan tinggi Agama. Semoga modul yangsingkat ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam mempelajarinya.segala upaya yang telah diusahakan, diharapkan mendapat perhatian bagi kita semua untukdapat meningkatkan kualitas diri dalam menimba ilmu pengetahuan.
Akhirnya, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh handai tolan atassumbangsih, baik saran ataupun masukan dalam memenuhi keseluruhan aspek penulisanmodul ini. Semoga kedepan dapat memulai kembali dengan modul atau buku yang berkualitaslainnya.
Penulis,
DAFTAR PEMBAHASAN
Pangantar ........................................................................................................................................Daftar Pembahasan ........................................................................................................................Pendahuluan ...................................................................................................................................
Topik 1Pengertian Hadis dan Kegunaannya dalam Studi Islam .................................................................
Topik 2Dalil-dalil kehujjahan Hadis dan fungsi Hadis terhadap Alquran .......................................
Topik 3Sejarah perkembangan Hadis sejak masa Nabi hingga periode pembukuan Hadis ..........
Topik 4Pengertian ilmu hadis riwayah, dirayah, dan cabang-cabang ilmu hadis lainnya .............
Topik 5Pembagian Hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad ..................................................
Topik 6Syarat-syarat Hadis Sahih dan Hasan .................................................................................
Topik 7Identifikasi Hadis Daif .........................................................................................................
Topik 8Pengertian Hadis Maudu’, sejarah kemunculan dan faktor yang melatarbelakanginya ...
Topik 9Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi (tahammul wal ada’) .......................
Topik 10Definisi dan fungsi Ilmu Rijalil Hadis ..................................................................................
Topik 11Definisi dan fungsi Ilmu Jarh wa Ta’dil ...............................................................................
Topik 12Inkar Sunah (pengertian, sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama) ............................
Topik 13Praktek Takhrij hadis ..........................................................................................................
Daftar Pustaka
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 1
STUDI PENGANTAR ILMU HADISSTAIN 1005 (2 sks)
Oleh: Triansyah Fisa, M.T.H.
PENDAHULUAN
Hadis adalah sumber hukum Islam pertama setelah Alquran. Tanpa menggunakan
hadis, syari’at Islam tidak dapat dimengerti secara utuh dan tidak dapat dilaksanakan. Setelah
berkedudukan sebagai sumber, ia juga berfungsi sebagai penjelas, pemerinci, dan penafsir
Alquran. Berdasarkan hal ini, maka kajian tentang Hadis memiliki kedudukan yang terpenting
dalam studi ilmu-ilmu sumber di dalam Islam.
Keharusan memedomani dan mengamalkan hadis adalah sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan perintah Allah swt1, karena apa yang dilakukan Nabi adalah manifestasi dan
penjabaran ajaran Islam secara faktual dan idial, disamping itu keberadaan hadis secara
orisinal ditengah kehidupan umat Islam adalah mutlak dibutuhkan. Sebab, tatkala tidak
ditemukan dalil-dalil yang jelas dan terperinci mengenai hukum sesuatu masalah maka hadis
adalah tempat rujukan selanjutnya untuk memecahkan dan menemukan hukum dan masalah
tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil dialog yang terjadi antara Mu’az bin Jabal dengan
Rasulullah saw tatkala beliau mengutus Mu’az untuk menjadi da’i dan hakim ke Negeri
Yaman (Siria)2.
Begitu besarnya pengaruh hadis dalam syariat agama mengharuskan kita untuk
mempelajari segala hal yang berkaitan dengannya untuk dapat memahami dari setiap
substansi Hadis tersebut. Langkah strategis yang akan ditempuh untuk memahami substansi
Hadis Nabi saw. berawal dari pemahaman terhadap pengertiannya, dalil kehujahannya hingga
sampai kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi hadis dalam masa sekarang, dan
termasuk permasalahan orang-orang yang meragukan keotentikan hadis tersebut.
1Al-Quran, Surah An-Nisa’ ayat 59.2Endang Saefuddin Anshari, Wawasan Islam, Bandung: Pustaka Salman, 1983, h. 32.
2 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 1._Pengertian Hadis dan Kegunaannya dalam Studi Islam
A. Pengertian
a. Hadis
Muḥaddiṡin (ulama ahli hadis) berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis.
Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terpengaruh oleh keterbatasan dan luasnya objek
peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan
dua macam definisi hadis, yakni: definisi yang terbatas di satu pihak dan definisi yang luas di
pihak lain.
1. Definisi hadis yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur Muḥaddiṡin, ialah:
Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan,
perbuatan, pernyataan (taqrir) maupun sifatnya.
Definisi ini mengandung empat unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan
sifat-sifat atau keadaan-keadaan nabi Muhammad saw. yang lain, kesemuanya hanya
disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan
tidak pula kepada tabi’in.
Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad
saw. disebut berita yang marfu’, yang disandarkan kepada sahabat disebut berita mauquf dan
yang disandarkan kepada tabi’iy disebut maqthu’.
2. Definisi hadis yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin,
tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu’kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi
juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’iy pun
disebut hadis. Dengan demikian hadis menurut definisi ini, meliputi segala berita yang
marfu’, mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu’ (disandarkan kepada tabi’iy),
sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfuẓ:
“Dikatakan (dari Ulama Ahli Hadis) bahwa sesungguhnya hadis itu bukan hanyasesuatu yang marfu’kan kepada Nabi saw saja, melainkan dapat pula disebutkan pada
3Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ (Mesir: Maktabah al-Ma’ārif, 2010), h. 17.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 3
apa yang ‘mauquf’ (yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan ataulainnya), dan pada apa yang ‘ maqthu’ ‘ (yang disandarkan kepada tabi’in).”
b. SunnahMenurut bahasa sunah mempunyai arti jalan, tabiat, syariat dan menerangkan.
Sedangkan menurut pengarang kitab “Lisanul Arab” –mengutip pendapat Syammar- sunah
pada mulanya berarti cara, jalan yang didahului oleh orang-orang dahulu kemudian diikuti
oleh orang-orang belakangan. Namun dalam kitab “Mukhtar al-Shahah” disebutkan sunah
secara etimologi berarti: Tata cara dan tingkah laku atau perilaku baik perilaku itu terpuji atau
tercela. Al-Thaqawi juga berpendapat sunah menurut etimologi adalah: Tata cara baik atau
buruk. Berbeda dengan arti etimologi itu, dalam Alquran sunah mengacu kepada arti
ketetapan atau hukum Allah.
Pengertian sunah menurut istilah, sebagaimana mendefinisikan hadis, dikalangan para
ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan samadengan hadis dan ada yang
membedakannya, bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan
istilah hadis.
Pengertian sunah menurut ahli hadis ialah:
“Segala yang bersumber dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir,tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup baik sebelum diangkat menjadi Rasulmaupun sesudahnya.”Menurut pengertian ini, kata sunah mempunyai arti yang sama dengan kata hadis
dalam pengertian terbatas atau sempit, sebagaimana dirumuskan oleh ulama hadis. Dengan
demikian jumlah sunah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata sunah menurut
definisi ahli uṣūl.
Menurut istilah ahli uṣūl fiqh, sunah ialah:
4Ramli Abdul Wahid, Studi Ilmu Hadis (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 3.5Al-Qur’an Surah. al-Nisā’ ayat 26; al-Hijjr ayat 13; al-Kahfi ayat 55; al_Isra’ ayat 77; al-Anfal ayat 38;
al-ahzab ayat 38 dan 62.
4 | Triansyah Fisa, M.T.H.
“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran, baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun taqrir-Nya yang pantas untuk dijadikan dalil dalam
penetapan hukum Islam.”
Sementara itu, Sunnah menurut ahli fiqh ialah:
“Segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw. selain yang difardhukan.”
Definisi lain menyebutkan bahwa sunah ialah: Sesuatu yang apabila dikerjakan lebih
baik dari pada ditinggalkan, kelebihan ini tidak berarti larangan atau ancaman karena
meninggalkannya, seperti sunah-sunah dalam shalat dan wudhu’. Pekerjaan sunah ini
membawa kelebihan sehingga dianjurkan untuk mengerjakannya dan tidak ada yang
mengharamkannya jika meninggalkannya.
Jadi menurut mereka sunah merupakan salah satu dari hukum yang lima yang
diterapkan pada perbuatan tiap mukhallaf baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun
sunah.
c. Khabar
Kata khabar berasal dari kata al-khabar dan jamaknya akhbāra yaitu: berita yang
disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pandang pendekatan bahasa kata
khabar sama artinya dengan hadis. Menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalanī sebagaimana dikutip as-
Suyuṭī, ulama yang mendefinisikan secara luas memandang bahwa istilah khabar sama
artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang marfu’, mauquf, dan
maqṭu’. Hal yang sama juga diungkapkan oleh al-Tirmiżī, hanya saja nama ikhbari digunakan
untuk menyebutkan orang yang menekuni tarikh-tarikh dan semisalnya sedangkan gelar
muhaddiṡ oleh para ulama diberikan kepada orang-orang yang secara khusus menekuni sunah.
Sedangkan menurut istilah ada tiga pendapat. Pertama, khabar sama dengan makna
hadis yaitu apa yang datang dari Rasulullah saw. Kedua, khabar adalah apa yang datang
selain dari Nabi saw. Ketiga, khabar ialah apa yang datang dari Nabi saw. dan selainnya,
sehingga berlaku istilah “Umumun wa Khususun Muthlaq” artinya tiap hadis dapat dikatakan
khabar, tetapi tidak setiap khabar dapat dikatakan hadis.
d. Atsar
Al-Aṡar menurut bahasa ialah bekasan, peninggalan, atau sisa sesuatu atau sama
artinya dengan khabar, hadis dan sunah. Sedangkan atsar menurut istilah terjadi perbedaan
pendapat antar ulama. Para fuqaha khurasan mengkhususkan istilah atsar untuk hadis mauquf
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 5
dan sebagian mereka mengkhususkan istilah khabar untuk hadis marfu’, akan tetapi yang
dipegang oleh muḥaddiṡīn adalah atsar yang sama artinya dengan khabar yaitu sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi saw., sahabat, dan tabiin. Karena atsar berasal dari kata “aṡaru al-
ḥadīṡ” –aku meriwayatkan hadis–. Pernyataan ini diperkuat oleh al-Ḥafiẓ al-‘Iraqi yang
menjuluki dirinya dengan al-Aṡari.
Ibnu Hajar juga menamakan kitabnya yang membahas mushthalah dengan judul
“Nukbat al-Fikr fi Mushthalah Ahli al-Atsar”.
e. Struktur Hadis
a. Sanad
Sanad atau thariq ialah jalan yang dapat menghubungkan matnu’l-hadis kepada
junjungan kita Nabi Muhammad saw.
Usaha seorang ahli hadis dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan
penjelasan kepada siapa hadis itu disandarkan, disebut meng-isnad-kan hadis. Hadis yang
telah diisnadkan oleh si-musnid (orang yang mengisnadkan) disebut dengan hadis Musnad.
Misalnya musnad Asy-Syihab dan musnad Al-Firdaus, merupakan kumpulan hadis yang telah
diisnadkan oleh Asy-Syihhab dan Al-Firdaus.
Selain itu Musnad dapat juga diartikan:
Hadis yang marfu’ lagi muttashil (sanadnya bersambung-sambung)
Nama Kitab yang menghimpun seluruh hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.
Pengertian Mukharrij
Mukharrij adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-
apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Sebuah hadis sampai
kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan dalam dewan-dewan Hadis, melalui
beberapa rawi dan sanad. Rawi yang terakhir Hadis yang termaksud dalam Sahih Bukhary
atau Sahih Muslim, ialah Imam Bukhary atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau
pengarang, bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan dari suatu Kitab Hadis,
pada umumnya membubuhkan nama rawi (terakhirnya) pada akhir matnul Hadisnya.
b. Matan
Kata matan atau al-matnu menurut bahasa ialah saluba wa irtafā’a min al-arḍi ‘tanah
yang meninggi’. Secara terminologi matan memiliki beberapa definisi yang pada dasarnya
maknanya sama, yaitu materi atau lafadz hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang
6 | Triansyah Fisa, M.T.H.
sangat sederhana misalnya disebutkan bahwa matan hadis itu ialah ujung atau tujuan sanad
(qayah al-sanad).
Pada definisi lain ada yang menyebutkan:
Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.
Ada juga yang menyebutkan:
Lafal-lafal hadis yang terkonstruksi maknanya.
B. Kegunaan Hadis dalam Studi Islam
Posisi Hadis sebagai fokus kajian telah memenuhi segala aspek studi keislaman baik
sejarah maupun kajian kekinian, bahkan diluar studi keislaman, hadis juga telah menjadi
fokus kajian –cara berpikir– sebagai acuan dalam bersikap. Kepentingan hadis sebagai
sumber hukum dalam syariat Islam pun telah berperan begitu penting. Harus diakui memang
–dalam penuturan Imam asy-Syāfi’ī–, untuk memahami dan mengamalkan kandungan
Alquran dibutuhkan informasi historis tentang bagaimana turunnya dan penjelasan/hadis
Rasul sebagai kewenangan yang mempunyai legalitas dalam mengulas dan memberi
penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang dimaksud,6 karena sunahnya tidak mungkin
bertentangan dengan Alquran.7
Sama halnya dengan Alquran, studi-studi keislaman yang berkembang sudah pasti
membutuhkan Hadis sebagai fokus utama dalam pengkajian dan fungsi serta kegunaannya
pun memiliki aturan yang sama dalam memahami Alquran sebagai objek kajian. Dalam
memberi penjelasan terkadang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatan, dan
adakalanya dengan kedua-duanya, penjelasan dimaksud berupa tafṣīl (penjelas), takhṣiṣ
(pengkhusus), dan taqyid (pembatasan).8
Dengan demikian kegunaan hadis dalam studi Islam dapat berupa bayan dalam
pengertian menjelaskan maksud dari suatu kajian yang sifatnya dapat menguatkan kajian
tersebut; takhṣiṣ dapat berupa pengkhususan suatu makna atau suatu masalah dari studi
6Imam asy-Sāfi’ī, ar-Risālah, terj. Masturi Irham dan Asmui Taman, Ar-Risalah, cet. 1 (Jakarta: Al-Kautsar, 2012), h. 12-14.
7Imam asy-Sāfi’ī, ar-Risālah, terj., h. 130.8Muh. Zuhri, Hadis Nabi ‘Telaah Historis dan Metodologis (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003),
h. 23.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 7
tersebut dan taqyid berfungsi sebagai pembatas kajian agar fokus pembicaraan lebih
mengarah.
8 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 2_Dalil-dalil Kehujahan Hadis dan Fungsi Hadis Terhadap Alquran
A. Dalil-dalil kehujjahan hadis
Yang dimaksud dengan kehujahan Hadis (hujjiyah hadis) adalah keadaan Hadis yang
wajib dijadikan hujah atau dasar hukum (al-dalil al-syar’i), sama dengan Alquran
dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Menurut Wahbah az-Zuhaili
dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dengan dalil-dalil
ini diluar ‘ijma adalah Imam asy-Syafi’I (w. 204 H) dalam kitabnya ar-Risalah dan al-Umm.
Islam menempatkan hadis setingkat dibawah Alquran, artinya hadis adalah dasar
Tasyri’ (penetapan hukum) sesudah Alquran yang dikuatkan oleh beberapa dalil.
1. Dasar Keimanan
Orang yang beriman kepada Allah haruslah beriman kepada ke-Rasulan Muhammad
saw. dengan menerima apa yang dia bawa. Dalam surat al-An’am: 124 Allah berfirman,
“untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan Rasulullah berasal dari Allah, ditegaskan
kembali” dalam surat an-Nahl: 35. Setelah tertanam dalam hati tentang kewajban percaya
kepada Rasul, dengan jelas Allah memerintahkan agar kita mengikuti apa yang dibawa oleh
beliau. Seperti dalam surat al-A’raf: 158.
2. Dasar Alquran
Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Alquran dan kembali kepada Rasul-
Nya. Ada dua buah ayat mengenai hal ini yakni al-Hasr: 7
3. Dasar Hadis
Banyak hadis yang menunjukkan harus mengikuti apa yang didatangkan Rasulullah:
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik: “Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang
jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat yaitu
Kitabullah dan Sunatullah”
b) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi: “Wajib atas
kamu mengikuti sunahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk.
Berpeganglah pada sunnah itu dan gigitlah dengan taringmu (peganglah kuat-kuat).”
c) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “Ketahuilah bahwa aku diberi kitab dan ada
yang serupa dengan Alquran.”
4. Dasar Ijma’
Semua umat Islam sepakat untuk mengamalkan Sunah Nabi. Diriwayatkan bahwa
Umar bin Khatab pernah berjongkok di depan Hajar Aswad seraya berkata: “Sungguh aku
tahu bahwa engkau (hajar aswad) hanyalah sebuah batu, seandainya aku tidak melihat
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 9
kekasihku (Rasulullah) menciummu dan mensalamimu pasti aku tidak akan mensalamimu
dan menciummu.”
Pernah suatu ketika Ibnu Umar ditanya, sebagai mana yang diriwayatkan oleh Musnad
Ahmad, kenapa tidak ditemukan tentang ketentuan salat bagi musafir dalam Qur’an, lalu
beliau menjawab,”Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad kepada kita yang sebelumnya
kita tak tahu apa-apa. Kita melakukan perbuatan sebagaimana beliau lakukan.”Dalam riwayat
lain Ibnu Umar menambahkan,”Kita sebelumnya dalam kesesatan kemudian Allah
memberikan petunjuk kepada kita maka dengan petunjuk itulah ita berpegang.”
Perkataan Imam asy-Syafi’i yang diungkap oleh as-Sya’rani dalam muqadimah al-
Mizanul Kubro, semuanya memberi pengertian bahwasegala pendapat Ulama harus kita
tinggalkan jika berlawanan dengan suatu hadis yang shohih. Dan kita harus sadar, walaupun
Alquran dan Hadis semuanya berasal dari Allah tapi kedudukan keduanya berbeda.
B. Kedudukan Hadis sebagi dasar hukum
Kedudukan Alquran sebagai dasar Tasyri’ yang pertama dan Hadis sebagai dasar
Tasyri’ yang kedua sesudahnya dengan alasan :
No Alquran Hadis
1Kitabullah: lafal dan maknanya dariAllah Swt.
Walaupun ia juga merupakan wahyu, tetapiperwujudannya oleh Nabi sendiri (manusia)
2 Sebagai hukum dasar.Sebagai pelaksanaannya, menerangkan ataumendatangkan apa yang belum didatangkanAlquran.
3
Diterima dengan jalan qath'i, artinyayang diterima memang benardemikian.
Diterima dengan jalan ẓanni (sangkaan),keyakinan kita kepada hadis hanya secaraglobal.
4Hadis sendiri menyatakan bahwa keduduk-annya adalah dibawah Alquran.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmiżi bahwa ketika Nabi mengutus Mu’adz bin
Jabal untuk menjadi hakim di Yaman beliau bertanya, “dengan apa engkau akan menetapkan
hukum?” Muadz menjawab, “Kitabullah” beliau berrtanya lagi, “Jika tak kau dapati?” Mu’adz
menjawab, “Sunah Rasulullah”, beliau bertanya lagi, “Kalau di sana pun tidak kau dapati?
“Mu’adz menjawab,” Aku akan berijtihad.
C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran
Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam,
antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan
10 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Alquran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat
umum dan global. Karena itu kehadiran hadis, sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk
menjelaskan keumuman isi Alquran tersebut.
Allah swt. menurunkan Alquran bagi umat manusia, agar Alquran ini dapat dipahami
oleh manusia, maka Rasul saw. diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara
melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya. Karena itu, fungsi hadis
Rasul saw. sebagai penjelas Alquran tersebut bermacam-macam, yaitu:
1. Bayan taqrir
Bayan taqrir disebut juga dengan bayan ta’kid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud
dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam
Alquran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memprkooh isi kandungan Alquran.
2. Bayan Tafsir
Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk
memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat mujmal
memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak dan
mengkhususkan terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum. Di antara contoh
tentang ayat-ayat Alquran yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan salat, puasa,
zakat, di syariatkannya jual beli, nikah, qisas dan sebagainya. Ayat-ayat Alquran tentang
masalah ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-
syarat atau halangan-halangannya. Karena itu, melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan
masalah-masalah tersebut.
3. Bayan at-Tasyri’Yang dimaksudkan dengan bayan tasyri’ adalah mewujudkan suatu hukum atau
ajaran-ajaran yang tidak di dapati dalam Alquran, atau dalam Alquran hanya terdapat pokok-
pokoknya saja. Hadis Rasul saw. Dalam segala bentuknya (baik yang qauli, fi’li, maupun
taqriri) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang
muncul, yang tidak terdapat dalam Alquran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang di ajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan
menunjukkan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya. Hadis-hadis Rasul saw. Yang
termasuk dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan
syuf’ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris
bagi seorang anak.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 11
4. Bayan Nasakh
Dalam bayan jenis ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ada yang
mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai nasikh terhadap sebagian hukum Alquran dan
ada juga yang menolaknya.
Kata nasakh secara bahasa berarti ibthal (membatalkan), izalah (menghilangkan),
tahwil (memindahkan), dan tagyir (mengubah). Para ulama mengartikan bayan nasakh ini
banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan
pendapat antara ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Menurut pendapat yang
dapat dipegang dari ulama mutaqaddimin, bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil
syara’ yang mengubah suatu hukum meskipun jelas, karena telah berakhir masa
keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syariat menurunkan ayat tersebut tidak di
berlakukan untuk selama-lamanya.
Jadi, intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang
datang terdahulu, karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan
nuansanya. Ketidak berlakukan suatu hukum harus memenuhi syarat-syaratnya yang
ditentukan, terutama masyarakat/ketentuan adanya nasakh dan mansukh. Pada akhirnya, hadis
sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Alquran dapat menghapus ketentuan dan
isi kandungan Alquran. Demikian menurut pendapat para ulama yang menganggap adanya
bayan nasakh. Kelompok yang membolehkan adanya nasakh jenis ini adalah golongan
mu’tazilah, hanafiyah, dan mazhab ibnu Hazm ad-Dahiri.
Hanya saja mu’tazilah membatasi fungsi nasakh ini hanya berlaku untuk hadis-hadis
yang mutawatir. Sebab al-kitab itu nasakhnya diriwayatkan secara mutawatir. Sementara
golongan hanafiyah yang dikenal agak longgar dalam hal nasakh Alquran dengan sunah ini,
tidak mensyaratkan hadisnya mutawatir, bahkan hadis masyhur (yang merupakan hadis ahad)
pun juga bisa menasakh hukum sebagian ayat Alquran. Bahkan Ibnu Hazm sejalan dengan
adanya naskh kitab dengan sunah ini meskipun dengan hadis ahad. Ibnu Hazm memandang
bahwa naskh termasuk bagian bayan Alquran. Sementara yang menolaj naskh jenis ini adalah
Imam asy-Syafi‘ī dan sebagian besar pengikutnya. Meskipun nask tersebut dengan hadis yang
mutawatir, termasuk diantaranya sebagian besar kelompok mazhab zahiriyah dan kelompok
khawarij.
12 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 3_Sejarah perkembangan Hadis sejak masa Nabi hingga periode pembukuan
Hadis
A. Sejarah Perkembangan Hadis
a. Pra Kodifikasi
1. Periode Rasulullah
Periode Rasulullah merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan
perkembangan hadis yang masanya cukup singkat jika dibandingkan dengan masa-masa
sesudahnya. Periode ini hanya berlangsung selama 22 tahun, mulai tahun 13 sebelum hijriah
bertepatan dengan tahun 610 masehi sampai dengan tahun 11 hijriah bertepatan dengan tahun
632 masehi. Periode ini adalah masa turunnya wahyu dan sekaligus sebagai masa
pertumbuhan hadis.
Pada periode ini sangat dituntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai
pewaris pertama ajaran Islam dalam menerima kedua sumber ajaran diatas, karena pada
tangan para sahabat-lah kedua-duanya harus terpelihara dan disampaikan kepada pewaris
berikutnya secara berkesinambungan.
Wahyu yang diturunkan Allah Swt. Kepada Rasulullah saw. dijelaskan melalui hadis-
nya dihadapan para sahabat sehingga apa yang didengar, dilihat dan disaksikan mereka
merupakan pedoman bagi amalan dan ubudiyah mereka sehari-hari.
2. Periode Sahabat
Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa
Khulafa’ al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi
Thalib) yang berlangsung sekitar 11 hijriahsampai dengan 40 hijriah. Masa ini juga disebut
dengan masa sahabat besar.
Karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan
penyebaran Alquran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang, dan kelihatannya
berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa
yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan (al-taṡabbut wa al-iqlāl min al-riwāyah).
3. Periode Tabi’inPada dasarnya periwayatan yang dilakukan oleh kalangan Tabi’in tidak berbeda
dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka, bagaimanapun, mengikuti jejak para
sahabat sebagai guru-guru mereka. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda
dengan yang diahdapi para sahabat. Pada masa ini Alquran sudah dikumpulkan dalam satu
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 13
mushaf. Di pihak lain, usaha yang telah dirintis oleh para sahabat, pada masa Khulafa’ al-
Rāsyidin, khususnya pada masa kekhalifahan Usman para sahabat ahli hadis menyebar ke
beberapa wilayah kekuasaan Islam. Kepada merekalah para tabi’in mempelajari hadis.
Ketika pemerintah dipegang oleh Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam sampai
meliputi Mesir, Persia, Iraq, Afrika Selatan, Samarkand dan Spanyol, disamping Madinah,
Mekkah, Basrah, Syam dan Khurasan. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan
Islam, penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut terus meningkat, sehingga masa ini
dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis (intisyār al-riwāyah ilā al-amshār).
b. Masa Kodifikasi
1. Abad Ke-II
Setelah Agama Islam tersebar dengan luas di masyarakat, dipeluk dan dianut oleh
penduduk yang bertempat tinggal di luar Jazirah Arabia, dan para shabat mulai terpencar di
beberapa dunia, maka terasalah perlunya hadis diabadikan dalam bentuk tulisan dan kemudian
dibukukan dalam dewan hadis. Urgensi ini menggerakkan hati Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul
‘Aziz – seorang Khalifah bani ‘Umayyah yang menjabat khalifah antara tahun 99 sampai
tahun 101 hijriah – untuk menulis dan membukukan (mendewankan) al-Hadis.
Motif utama Khalifah ‘umar ibn ‘Abdul ‘Aziz berinisiatif demikian:
a. Kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang sudah-
sudah. Karena beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis dari perbendaharaan
masyarakat, disebabkan belum didewankannya dalam dewan hadis.
b. Kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memlihara hadis dari hadis-hadis
maudhu’ yang dibuat oleh orang –orang untuk mempertahankan idiologi golongannya dan
mempertahankan mazhabnya, yang mulai tersiar sejak awal bersirinya kekhilafahan ‘Ali
bin Abi Thalib r.a.
c. Alasan tidak terdewannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah saw. dan Khulafaur
Rasyidin, karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Alquran, telah hilang,
disebabkan Alquran telah dikumpulkan dalam satu mush-haf dan telah merata diseluruh
pelosok. Is telah dihafal dan diserapkan di hati sanubari beribu-ribu orang.
d. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi peperangan
antara Muslim dengan orang Kafir, demikian juga perang saudara orang-orang Muslim,
yang kian hari kian menjadi-jadi, yang sekaligus berakibat berkurangnya jumlah ulama
hadis, maka pada saat itu konfrontasi tersebut benar-benar terjadi.
14 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Untuk menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya hadis dan memelihara hadis dari
bercampurnya dengan hadis-hadis palsu, beliau menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan
ulama yang memegang kekuasaan di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan al-Hadis.
Instruksinya berbunyi:
“Teliti hadis Rasulullah saw. kemudian kumpulkan!” (Riwayat Abu Nu’aim)
Ciri-ciri Kitab Hadis
Seiring dengan kemauan yang keras untuk mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya,
mereka tidak menghiraukan atau belum sempat menyeleksi apakah yang mereka dewankan itu
hadis Nabi semata-mata ataukah termasuk juga di dalamnya fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in.
Bahkan lebih jauh dari itu mereka belum mengklasifisir kandungan nash-nash hadis menurut
kelompok-kelompoknya.
Dengan demikian karya ulama abad kedua ini masih bercampur aduk antara hadis
Rasulullah dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in. Walhasil, bahwa kitab-kitab hadis karya
ulama-ulama tersebut belum ditapis antara hadis-hadis yang marfu’, mauquf dan maqthu’, dan
di antara hadis yang sahih, hasan dan daif.
Kitab-kitab Hadis Yang Masyhur
Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:
b. Al-Muwaththa’. Kitab ini disusun oleh Imam Malik pada tahun 144 H, atas anjuran
Khalifah al-Mansur. Jumlah hadis 1720 buah. As-Suyuthi mensyarahkan kitab tersebut
dengan nama Tawiru al-Hawalik dan al-Khaththaby.
c. Musnadu asy-Syāfi‘ī. Isi kitab seluruh hadis yang tercantum dalam kitab beliau yang
bernama al-Umm.
d. Mukhtalif al-Ḥadīṡ. Karya Imam asy-Syāfi‘ī. Dalam kitabnya beliau menjelaskan cara-
cara menerima hadis sebagai hujjah, dan menjelaskan cara-cara untuk mengompromikan
hadis-hadis yang tampaknya kontradiksi (berseberangan) satu sama lain.
2. Abad ke-III
Di permulaan abad ketiga para ahli hadis berusaha menyisihkan al-hadis dari fatwa-
fatwa sahabat dan tabi’in. Mereka berusaha membukukan hadis Rasulullah semata-mata.
Untuk tujuan yang mulia ini mereka mulai menyusun kitab-kitab Musna yang bersih dari
fatwa-fata. Bangulah ulama-ulama ahli hadis seperti: Musa al-‘Abbasy, Musaddad al-Bashry,
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 15
Asad bin Musa dan Nu’aim bin Hammad al-Khaza’iy menyusun kitab-kitab Musnad.
Kemudian menyusul pula Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Kendatipun kitab-kitab
hadis permulaan abad ketiga ini sudah menyisihkan fatwa-fatwa, namun masih mempunyai
kelemahan, yakni tidak atau belum menyisihkan hadis-hadis daif, termasuk juga hadis
maudhu’ yang diselundupkan oleh golongan-golongan yang bermaksud hendak menodai
agama Islam.
Karena adanya beberapa kelemahan kitab-kitab hadis tersebut, bergeraklah ulama-
ulama ahli hadis pertengahan abad ketiga untuk menyelamatkannya. Mereka membuat
kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan suatu hadis itu apakah sahih atau daif.
Para rawi hadis tidak luput menjadi sasaran penelitian mereka, untuk diselidiki kejujurannya,
kehafalannya dan lain sebagainya.
Kitab-kitab hadisnya
Pendewan-pendewan hadis sahih semata-mata pada pertengahan abad ketiga antara lain dapat
dikemukakan:
a. Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī (194 – 256 H) dengan kitab hadisnya yang terkenal
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī atau al-Jami‘ aṣ-Ṣaḥīḥ, menurut nama yang beliau berikan.
b. Muslim bin Ḥajjāj bin Ḥasan al-Qusyairy (204 – 261 H.) dengan kitabnya bernama Ṣaḥīḥ
al-Muslim atau al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir min as-Sunan, menurut nama aslinya.
Kitab tersebut berisi hadis sebanyak 7.273 hadis, termasuk hadis yang berulang-ulang.
Jika tanpa hadis yang berulang-ulang hanya berjumlah 4000 buah. Syarah Sahih Muslim
yang terkenal ialah Minhaj al-Muhaddiṡin hasil karya Muhyiddin Abu Zakariya bin Syarif
an-Nawawy. Di antara mukhtasharnya ialah Mukhtasar al-Mundziry.
Di samping kitab-kitab Musnad (yang mengandung segala rupa hadis; baik sahih,
hasan maupun daif), kitab-kitab Sahih (yang berisikan hadis-hadis sahih saja),muncul pula
pada abad ketiga ini kitab-kitab Sunan (yang mencakup seluruh hadis, kecuali hadis yang
sangat daif dan mungkar). Seperti Sunan Abu Daud., sunan at-Tumudzy, Sunan an-Nisā’i,
dan Sunan Ibn Majah.
3. Abad ke-IV
Kalau pada abad-abad sebelumnya al-Hadis berturut-turut mengalami masa
periwayatan, penulisan (pendewanan) dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan
tabi’in, dan hadis yang telah didewankan oleh ulama Muqtaqaddimin (ulama abad kesatu
16 | Triansyah Fisa, M.T.H.
sampai ketiga) tersebut mengalami sasaran baru, yakni dihafal dan diselidiki sanadnya oleh
ulama muta-akhkhirin (ulama abad keempat dan seterusnya).
Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis yang telah
terdewan itu, hingga tidak mustahil sebagian dari mereka sanggup menghafal beratus-ratus
ribu hadis. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis,
seperti gelar keahlian al-Hakim, al-Hafidz dan lain sebagainya.
Abad keempat ini merupakan abad pemisah antara ulama Mutaqaddimin, yang dalam
menyusun kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi’in
pengahafadh hadis dan kemudian menelitinya sendiri, dengan ulama Mutaakhkhirin yang
dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis, mereka hanya menukil dari kitab-kitab yang
telah disusun oleh ulama Mutaqaddimin.
Kitab-kitab Yang Masyhur
1. Mu’jam al-Kabir,
2. Mu’jam al-Ausath, dan
3. Mu’jam ash-Shaghir, ketiga-tiganya adalah karya Imam Sulaiman bin Ahmad ath-
Thabrany (meninggal tahun 360 H.)
4. Sunan ad-Daruquthny, karya Imam ‘Abdul Hasan ‘Ali bin ‘Umar bin Ahmad ad-
Daruquthny (306 – 385 H)
5. Sahih Abi ‘Auwanah, karya Abu ‘Auwanah Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Asfarainy
(meninggal tahun 345 H)
6. Sahih Ibnu Khudzaimah, karya Ibnu Khudzaimah Muhammad bin Ishaq (meninggal tahun
316 H).
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 17
Topik 4_ Pengertian ilmu hadis riwayah, dirayah, dan cabang ilmu hadis lainnya
A. Perkembangan Ilmu Hadis
a. Pengertian Ulumul Hadis
Yang dimaksud dengan ilmu hadis, menurut ulama mutaqaddimin adalah:
“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis samapai
kepada Rasul saw. dari segi hal ihwal para perawinya, kedhabitan, dan dari bersambung
tidaknya sanad, dan sebagainya.”
Pada perkembangan selanjuutnya, oleh ulama mutaakhkhirin, ilmu hadis ini dipecah
menjadi dua, yaitu Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah. Pengertian yang diajukan
oleh ulama mutaqaddimin itu sendiri, oleh ulama mutaakhkhirin dimasukkan kedalam
pengertian ilmu Dirayah.
1. Ilmu Hadis Riwayah
Yang dimaksud dengan ilmu Hadis Riwayah, ialah:
“Ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. baikberupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi’at maupun tingkah lakunya.”
Ibn al-Akfānī, sebagaimana dikutip oleh al-Suyūthī, mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan ilmu hadis Riwayah ialah:
“Ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi saw. baikperiwayatannya, maupun penulisan atau pembukuan lafadh-lafadhnya.”
2. Ilmu Hadis Dirayah
Ilmu Hadis Dirayah biasa juga disebut sebagai Ilmu Musthalah al-Hadīts, Ilmu Ushūl
al-Hadīts, Ulūm al-Hadīts, dan Qawā’id al-Tahdīts. Al-Tirmisī mendefinisikan ilmu ini
dengan:
18 | Triansyah Fisa, M.T.H.
“Undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, caramenerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain.”Ibnu al-Akfani mendefinisikan ilmu ini sebagai berikut:
“Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam,dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya,macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya.”Yang dimaksud dengan:
- Hakikat Periwayatan adalah penukilan hadis dan penyandarannya kepada sumber hadis
atau sumber berita.
- Syarat-syarat periwayatan ialah penerimaan perawi terhadap haits yang akan diriwayatkan
dengan bermacam-macam cara penerimaan, seperti melalui al-Samā’ (pendengaran), al-
Qirā’ah (pembacaan), al-Washiah (berwasiat), al-Ijāzah (pemberian izin dari perawi).
- Macam-macam periwayatan ialah membicarakan sekitar bersambung dan terputusnya
periwayatan dan lain-lain.
- Hukum-hukum periwayatan ialah pembicaraan sekitar diterima atau ditolaknya suatu
hadis.
- Keadaan para perawi ialah pembicaraan sekitar keadilan, kecacatan para perawi, dan
syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan hadis.
- Macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada
kitab-kitab tashūf, kitab tasnīd, dan kitab mu’jam.
Ada pula ulama yang menjelaskan, bahwa Ilmu Hadis Dirayah ialah:
“Ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan, yang dengannya kami dapat membedakan antara hadis yang sahih yangdisandarkan kepada Rasul saw. dan hadis yang diragukan penyandarannya kepadanya.”
b. Sejarah Perkembangan
Ilmu ini telah tumbuh sejak zaman Rasul saw. masih hidup. Akan tetapi ilmu ini terasa
diperlukan setelah Rasul wafat, terutama sekali ketika umat Islam memulai upaya
mengumpulkan hadis dan mngadakan perlawatan yang mereka lakukan, sudah barang tentu
secara langsung atau tidak, memerlukan kaidah-kaidah guna menyeleksi periwayatan hadis.
Di sinilah Ilmu Hadis Dirayah mulai terwujud dalam bentuk kaidah-kaidah yang sederhana.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 19
Pada perkembangan berikutnya kaidah-kaidah itu semakin disempurnakan oleh para
ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, baik mereka yang mengkhususkan
diri dalam mempelajari bidang hadis, maupun bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi satu
disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
Dalam sejarah perkembangan hadis tercatat, bahwa ulama yang pertama kali berhasil
menyusun ilmu ini dalam suatu disiplin ilmu secara lengkap, adalah al-Qādhi Abu
Muhammad al-Ramahurmuzi (w. 360 H) dengan kitabnya al-Muhaddits al-Fāshil baina al-
Rāwi wa al-Wa’i. Kemudian muncul al-Hākim Abu ‘Abdillah al-Naisābūri (321-405 H)
dengan kitabnya Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadīts. Setelah itu, muncul Abu Nu’aim Ahmad bin
‘Abdillah al-Asfahani (336-430 H). berikutnya al-Khatīb al-Baghdādī (w. 463 H) melalui
Kitabnya “al-Kifāyah fi Qawānin al-Riwāyah” dan al-Jāmi’ li Adabi al-Syaikh wa al-Sāmi’;
al-qādhi ‘Iyad bin Mūsa (w. 544 H) dengan kitabnya yang bernama al-‘Ilma fi Dhabt al-
Riwāyah wa Taqyīd al-Asmā’; Abu Hafs Umar bin Abd Majid al-Mayanzi (w. 580 H) dengan
kitabnya Mā Lā Yasi’u al-Muhaddits Jahlahu; Abu Amr dan Usman bin ‘Abd al-Rahman
alSyahrazury (w. 643 H) dengan kiabnya Ulūm al-Hadis yang dikenal dengan Muqaddimah
ibn al-Shalāh. Kitab yang terakhir ini oleh para ulama berikutnya disyarahkan dan dibuat 27
mukhtasyar-nya, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh ulama generasi berikutnya.
c. Cabang-cabang Ulumul Hadis
Dari hadis Riwayah dan Dirayah, pada perkembangan berikutnya, mucullah cabang-
cabang ilmu hadis lainnya, antara lain:
1. Ilmu Rijāl al-Hadis,
2. Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil,
3. Ilmu Tarikh al-Ruwah,
4. Ilmu ‘Ilal al-Hadis,
5. Ilmu al-Nasih wa al-Mansukh,
6. Ilmu Asbab Wurud al-Hadis,
7. Ilmu Gharib al-Hadis,
8. Ilmu Thabaqah (Tabaqah al-Ruwah),
9. Ilmu Mukhtalif al-Hadis,
10. Ilmu Tawarikh al-Mutun.
20 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 5_Pembagian Hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad
A. Klasifikasi Hadis
a. Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas
Para Ulama membagi hadis menjadi dua bagian, mutawātir dan āhad.
1. Hadis Mutawatir
Mutawatir menurut bahasa adalah mutatābi yang datang berikutnya atau beriring-
iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya.
Sedangkan pengertian hadis mutawātir menurut istilah, terdapat beberapa definisi, antara lain
sebagai berikut:
“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil merekabersepakat terlebih untuk berdusta.”Ada juga yang mengatakan:
“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil merekabersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiaptingkat (Thabaqāt).”Sementara Nur ad-Din ‘Atsar mendefinisikan
“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatanmereka untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan padapanca indra.”
Syarat-syarat Hadis Mutawatir
1. Pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca
indra. Yakni warta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau
penglihatan sendiri.
2. Jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketenteuan yang tidak memungkinkan mereka
bersepakat bohong.
a. Abu al-Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Diqiyaskan dengan
banyaknya saksi yang diperlukan hakim.
b. Ashhabu al-Syafi’i menentukan minimal 5 orang, karena mengqiyaskan dengan
jumlah para Nabi ulul azmi.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 21
c. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang, berdasarkan firman Allah
dalam surah al-Anfal 65, tentang sugesti Allah kepada orang-orang mukmin yang
tahan uji, yang hanya dengan berjumlah 20 orang saja mampu mengalahkan orang
kafir sejumlah 200 orang.
d. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang, karena
mereka mengqiyaskan dengan firman Allah surah al-Anfal 64.
3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam thabaqat (lapisan) pertama dengan
jumlah rawi-rawi dalam thabaqat berikutnya. Kalau suatu hadis diriwayatkan oleh sepuluh
sahabat umpamanya, kemudian diterima oleh lima orang tabi’iy dan seterusnya hanya
diriwayatkan oleh dua orang tabi’ al-tabi’in, bukan hadis Mutawatir. Sebab jumlah rawi-
rawinya tidak seimbang antara thabaqah pertama, kedua dan ketiga.
Macam-macam mutawatir
Hadits mutawatir ada tiga macam, yaitu :
a. Mutawatir Lafẓi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafa dan makna yang sama, serta
kandungan hokum yang sama, contoh :
Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, makahendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di api neraka.9
Menurut Al-Bazzar, hadits ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi menyatakan
bahwa hadits ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat.
b. Mutawatir Ma‘nawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadits yang
diriwayatkan dengan lafal yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna
yang sama sedang lafalnya tidak. Contoh hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi
Muhammad saw. mengangkat tangannya ketika berdo‘a:
Abu Musa Al-Asy‘ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa kemudian mengangkat
kedua tangannya dalam berdo‘a hingga nampak putih kedua ketiaknya, dan Anas berkata:
bahwasannya Nabi saw., tidak mengangkat kedua tangannya, kecuali saat melakukan do‘a
dalam sholat istisqa'. (Al-Bukhārī dan Muslim)
9Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz. I, no. 4, h. 13
22 | Triansyah Fisa, M.T.H.
c. Mutawatir Amali, yakni amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad
saw., kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh Tabi‘in, dan
seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh, hadits-hadits nabi tentang shalat
dan jumlah rakaatnya, shalat id, shalat jenazah dan sebagainya. Segala amal ibadah yang
sudah menjadi ijmak di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir amali.
2. Hadis Ahad
Suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Mutawatir disebut hadis Ahad.
Ulama Muḥaddiṡin mendefinisikannya dengan:
“Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.”
Klasifikasi Hadis Ahad
Para Muhadditsin memberikan nama-nama tertentu bagi hadis Ahad mengingat
banyak-sedikitnya rawi-rawi yang berada pada tiap-tiap thabaqat, antara lain:
a. Hadis Aḥad Masyhur
“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat
mutawatir.”
Macam-macam Hadis Masyhur
Hadis masyhur terbagi kepada:
1. Masyhur di kalangan para Muhadditsin dan lainnya (golongan ulama ahli ilmu dan
orang umum),
2. Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya masyhur di kalangan ahli
hadis saja, atau ahli fiqh saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, atau lain
sebagainya,
3. Masyhur di kalangan orang-orang umum saja.
b. Hadis Aḥad ‘Aziz
“Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat padasatu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.”
c. Hadis Aḥad Garib
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 23
“Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan,dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”Klasifikasi Hadis Garib
Hadis garib terbagi kepada dua macam, yaitu:
1. Garib Mutlak (Fard)
Apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalianya,
penyendirian dalam hadis ini harus berpangkal di tempat aṣlus-sanad, yakni tabiin, bukan
pada sahabat. Sebab yang menjadi objek perbincangan dalam penelitian hadis adalah
perawi setelah para sahabat, sementara para sahabat telah dinilai sebagai orang yang adil.
2. Garib Nisby
Yang dimaksud garib nisby ialah penyendirian perawi yang berkenaan dengan sifat atau
keadaan tertentu seorang rawi, yang terjadi dalam beberapa kemungkinan: tentang sifat
keadilan dan kedabitannya (terpercaya); tentang kota atau tempat tinggal tertentu; tentang
meriwayatkannya dari rawi tertentu.
b. Hadis Ditinjau dari Segi Kualitas
Dalam tinjauan kualitas sanad hadis, dikelompokkan menjadi dua yaitu: maqbul (diterima),
dan mardud (ditolak). Kelompok hadis dengan tinggkatan maqbul termasuk sahih dan hasan,
sedang kelompok hadis dengan tinggkatan mardud hanya dalam kategori daif.
24 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 6_ Syarat-syarat Hadis Sahih dan Hasan
1. Hadis Sahih
“Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnyabersambung-sambung, tidak ber’illat dan tidak janggal.”
Syarat-syarat Hadis Sahih
Menurut definisi diatas, bahwa suatu hadis dapat dinilai sahih, apabila telah memenuhi
lima syarat sebagai berikut:
1. Rawinya bersifat ‘adil,
2. Sempurna ingatan,
3. Sanadnya tidak terputus,
4. Tidak ber’illat (cacat), dan
5. Tidak terdapat kejanggalan (syudzudz)
Klasifikasi Hadis Sahih
Terbagi kepada dua bagian:
1. Sahih liżātih
Hadis yang terpenuhinya syarat sahihnya sanad dan matan, sebagaimana yang disebutkan
dalam definisi hadis Sahih.
2. Sahih ligairih
Hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang ḥafiẓ dan ḍabit tetapi mereka masih terkenal
kejujurannya, hingga karenanya berderajat hasan. Kemudian terdapat jalur sanad lain yang
serupa atau lebih kuat atau yang dikenal dengan syahid dan mutabi’, yang dapat menutupi
kekurangan yang menimpa sanad hadis tersebut, sehingga hadis dengan derajat hasan tadi
naik menjadi sahih dalam kategori ligairihi.
2. Hadis Hasan
At-Tirmiżī mendefinisikan hadis hasan dengan:
“Ialah hadis yang pda sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapatkejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyaibanyak jalan) yang sepadan maknanya.”Jumhur ulama Muhadditsin mendefinisikan sebagai berikut:
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 25
“Hadis yang dinukilkan oleh seorang adil, tapi tidak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat ‘illat serta kejanggalan matannya.”
Klasifikasi Hadis Hasan
Sama halnya dengan hadis sahih, hadis hasan terbagi kepada dua bagian:
1. Hasan liżātih
Definisi hasan liżatih sebagai hadis hasan pada umumnya.
2. Hasan ligairih
Hasan ligairih adalah hadis yang tidak sepi dari seorang mastur –tidak nyata keahliannya–
, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak terlihat adanya sebab yang menjadikannya
fasik dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatn yang seisal dan semakna
dari sesuatu segi lainnya. Dalam arti alin, yakni hadis daif yang bukan sebab rawinya
pelupa, kemudian mempunyai mutabi’ dan syahid, sehingga derajat hadisnya naik menjadi
hasan ligairih.
Catatan:Perlu diingat bahwa derajat sanad hadis dari masing-masing hadis tersebut masih tetap sama(yang hasan akan tetap hasan dan daif akan tetap daif), tidak berubah. Namun, yang berubahderajatnya adalah matan hadis tersebut, disebabkan ada hadis lain yang meriwayatkan denganlafal atau makna yang serupa.
26 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 7_Identifikasi Hadis Daif
A. Definisi Hadis Daif
Dalam pengertiannya hadis daif diartikan sebagai hadis yang lemah dengan sebab terputusnya
sanad dan atau hilang kredibilitasnya seorang rawi dengan sebab-sebab tertentu. Secara umum
dapat didefinisikan hadis daif sebagai berikut:
“Ialah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis
hasan.”
Klasifikasi Hadis Daif
a. Dari jurusan sanad diperinci menjadi dua bagian:
Pertama: “Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilannya maupun
kehafalannya.”
Kedua: “Ketidak bersambungnya sanad”, dikarenakan seorang rawi atau lebih, yang
digugurkan atau saling tidak bertemu satusama lain.
b. Dari jurusan matan
Hadis daif yang disebabkan suatu sifat yang terdapat pada matan, ialah:
1. Hadis Mauquf
2. Hadis Maqthu’
Macam-macam Hadis Daif
1. Berdasarkan Kecacatan Rawi dan Kedabitannya
a. Hadis Mauḍu’
Hadis yang dibuat oleh seorang pendusta yang disengaja maupun tidak dengan tujuan
tertentu dan kemudian disandarkan kepada Rasulullah saw. secara umum disebut hadis
palsu. (penjelasan detailnya pada topik berikutnya)
b. Hadis Matruk
Hadis yang diriwayatkan hanya melalui satu jalur yang di dalamnya terdapat seorang
periwayat yang tertuduh pendusta, fasiq, atau banyak lalai.
c. Hadis Munkar dan Ma’ruf
10Periksa penjelasannya pada poin c dari topik ini.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 27
Hadis yang diriwayatkan oleh orang lemah yang menyalahi riwayat orang yang lebih
terpercaya dari padanya. Definisi ini kebalikan dari hadis ma’ruf, yaitu hadis yang
diriwayatkan oleh orang ṡiqah yang menyalahi riwayat orang daif.
d. Hadis Mu’allal
Hadis yang kelihatannya tidak mengandung cacat (sanad atau matan atau keduanya),
namun setelah diadakan penelitian mendalam ternyata ada cacatnya. Umumnya terjadi
pada sanad, seperti sengaja menyambung sanad yang sebenarnya terputus.
e. Hadis Mudraj
Hadis yang didalamnya terlihat adanya penambahan (yang sebenarnya tidak termasuk
hadis), seperti penambahan kalimat atau pernyataan (matan) oleh perawi itu sendiri,
hingga akhirnya disalahpahami bahwa pernyataan itu termasuk hadis Nabi saw.
f. Hadis Maqlub
Hadis yang periwayatannya menggantikan sebagiannya dengan yang lain dan atau
ditukar, baik yang ditukar itu sanad atau matan, sengaja ataupun tidak, karena sebab
mendahulukan dan mengakhirkan.
g. Hadis Muḍṭarrib
Hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur yang sanad atau matannya saling
bertentangan, baik periwayat itu satu atau beberapa orang. Dengan kata lain, hadis
yang ditangguhkan kehujahannya sebagai dalil hingga ditemukan hadis lain yang
dapat digunakan sebagai penguat hadis tersebut.
h. Hadis Mubham, Majhul dan Mastur
Hadis mubham adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi
yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan.
Jika nama seorang rawi disebutkan dengan jelas, tetapi ia bukan tergolong
orang yang sudah dikenal keadilannya dan tidak ada rawi ṡiqah yang meriwayatkan
hadis darinya kecuali seorang saja, maka rawi ini disebut majhulul-‘ain, sementara
hadis yang diriwayatkannya disebut hadis majhul. Kemudian rawi dikenal keadilan
dan kedabitannya dari periwayatan orang yang ṡiqah, tetapi beluma ada suatu
kesepakatan tentang penilai rawi itu, rawi ini disebut majhulul-ḥal, dan hadis
diriwayatkan olehnya disebut hadis mastur.
i. Hadis Syāż dan Maḥfūẓ
Hadis yang diriwayatkan oleh orang terpercaya, tetapi bertentang dengan hadis yang
diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya lagi. Disebut syāż apabila terdapat di
28 | Triansyah Fisa, M.T.H.
dalamnya periwayat yang menyendiri dan bertentangan. Sementara, hadis yang lebih
kuat sebagai bandingannya disebut maḥfūẓ.
j. Hadis Mukhtalaṭ
Mukhtalith adalah hadis yang rawinya buruk hafalannya (hafalannya lebih sedikit dari
lupanya) dengan sebab tertentu seperti telah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau
hilang kitab-kitabnya. Dalam kehujahan hadis yang diriwayatkannya ditolak, tetapi
apabila periwayatan sebelum mengalami ikhtilāṭ, hadisnya diterima.
2. Berdasarkan Gugurnya Rawi
a. Hadis Mu’allaq
Hadis yang salah satu atau keseluruhan sanadnya dihilangkan dan hanya menyebutkan
perawi terakhir.
b. Hadis Mursal
Hadis yang disandarkan kepada Rasul oleh tabiin tanpa menyebutkan nama Sahabat
yang membawa hadis itu.
c. Hadis Mudallas
Mudallas atau tadlīs artinya menyimpan/menyembunyikan aib. Hadis yang di
dalamnya terdapat sesuatu yang disembunyikan, seperti sanadnya ataupun gurunya
dengan tujuan agar orang lain tidak mengetahui kecacatan pada gurunya.
d. Hadis Munqaṭi'
Hadis yang sanadnya terdapat salah seorang perawi yang digugurkan (tidak disebutkan
namanya), baik di awal maupun di akhir periwayatannya.
e. Hadis Mu’ḍal
Hadis yang dalam sanadnya terdapat dua orang periwayat atau lebih secara berturut-
turut tidak disebutkan namanya, seperti perkataan seorang penulis atau pembicara dari
kalangan fuqaha “Rasulullah bersabda begini dan begitu...” sementara perawi
sebelumnya tidak disebutkan atau telah dibuang.
c. Hadis Ditinjau Dari Sumbernya
Sumber hadis terbagi atas tiga, yaitu
1. Hadis Marfu’
Hadis Marfu’ yaitu hadis yang sampai sanadnya kepada Nabi, baik perkataan,
perbuatan atau taqrir; sanadnya berhubungan ataupun terputus.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 29
Adapun hadis marfu’ itu belum dapat kita katakan sahih, hasan, daif dan belum pula
boleh dikatakan sabda Nabi atau perkataan sahabat. Dengan menyelidiki dalam kitab-kitab
hadis, dapatlah kita katakan hadis Marfu’ itu sahih, hasan atau daif, begitu pula hadis itu
sabda Nabi atau perkataan sahabat.
2. Hadis Mauquf
“Berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu
perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.”
3. Hadis Maqthu’
“Ialah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi’iy serta dimauqufkanpadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak.”
Secara bahasa kata Tabi’in merupakan bentuk jamak (Plural) dari Tabi’i atau Tabi’.
Tabi’ merupakan Ism Fa’il dari kata kerja Tabi’a. Bila dikatakan, Tabi’ahu fulan, maknanya
Masya Khalfahu (Si fulan berjalan di belakangnya).
Secara istilah adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Muslim dan
meninggal dunia dalam Islam pula. Ada yang mengatakan, Tabi’i adalah orang yang
menemani sahabat.
30 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 8_Pengertian Hadis Mauḍu’, Sejarah dan Faktor Kemunculan
A. Pengertian Mauḍū’
Mauḍū’ merupakan isim maf’ul dari kata waḍa’a dengan arti yang berbeda-beda seperti
“meletakkan”, “menggugurkan”, “meninggalkan”, “membuat dan lain-lain. Sehingga dalam
istilah ilmu hadis, hadis mauḍū’ adalah:
Hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta), yang disandarkan kepadaRasulullah saw. secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak.
B. Cara Mengetahui Hadis Mauḍū’
Hadis mauḍū’ pada dasarnya dapat diketahui dengan memperhatikan hal-hal berikut:
d. Berdasarkan pengakuan para pembuat hadis itu sendiri,
e. Perawinya diketahui sebagai seorang pendusta, dan hadis yang diriwayatkannya tidak
diriwayatkan oleh para perawi terpercaya;
f. Ditemukan indikasi bahwa perawi itu memalsukan hadis, misalnya seorang Syiah
Rafidah meriwayatkan hadis tentang ahlul bait;
g. Makna atau lafalnya rusak;
h. Makna dan lafalnya bertentangan dengan Alquran, hadis, hal-hal yang mudah dipahami
dalam agama dan akal sehat. Contoh:
Anak zina itu tidak dapar masuk surga sampai tujuh keturunan.
Makna hadis ini bertentangan dengan surat al-An’am: 164,
Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
C. Sejarah Munculnya Hadis Mauḍū’
Ulama berbeda pendapat di seputar awal terjadinya pemalsuan hadis. Suatu pendapat
mengatakan bahwa pemalsuan itu telah terjadi sejak masa Rasul saw., segolongan lagi
berpendapat bahwa terjadinya pemalsuan itu sejak tahun 40 Hijriah. Di sampign itu ada juga
yang mengatakan, terjadinya pemalsuan itu akhir abad pertama Hijriah,. Perbedaan pendapat
ini terjadi karena tidak adanya keterangan nash yang jelas, yang berkaitan dengan kasus ini.
Pendapat pertama, dikemukakan oleh Ahmad Amin, Shalah ad-Din al-Idlibi, dan
Hasyim Ma’ruf al-Husaini. Ahmad Amin beralasan adanya Hadis yang mengatakan,
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 31
“Barangsiapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka tempat kembalinya adalah
neraka.” Menurutnya, dengan munculnya Hadis ini tergambar bahwa kemungkinan pada
zaman Nabi saw. telah terjadi pemalsuan hadis. Di sini ia memandang bahwa pemalsuan hadis
merupakan penyebab di sabdakannya Hadis itu. Namun alasan ini dikritik oleh Mustafa as-
Siba’I sebagai suatu dugaan dan tidak mempunyai alasan historis dan tidak ditemukan di
dalam kitab-kitab asbab al-wurud.
Berdasarkan keterangan yang dijelaskan Utang Ranuwijaya bahwa Shalah al-Din al-Idlibi
mengemukakan alasan lain, yaitu adanya dua buah Hadis riwayat at-Tahawi dan ath-Thabrani
tentang peristiwa pemalsuan tersebut. Pada masa Rasul saw. Ada seseorang
D. Faktor Munculnya Hadis Mauḍū’
Di antara faktor munculnya hadis palsu di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Secara eksternal antara lain disebabkan keinginan dari pihak non muslim untuk melemkahkan
Islam dari ajaran sumbernya, yaitu Hadis Nabi. Secara internal adanya golongan munafik
untuk kepentingan politik tertentu, seperti mendukung aliran-aliran dalam ushul ad-din;
adanya golongan sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah secara berlebih-lebihan; untuk
mencari muka kepada penguasa; semata-mata untuk memuaskan nafsu dan kesenangan
pribadinya; karena gejala linglung pada usia lanjut; dan katena untuk memikat orang agar
tertarik terhadap nasihat-nasihatnya.
E. Usaha Para Ulama Dalam Memberantas Hadis Mauḍu’
Beberapa hal berikut yang telah dilakukan oleh para ulama dalam memelihara sunah dan
membersihkannya dari pemalsuan hadis;
1. Mengisnadkan hadis;
2. Meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis;
3. Memerangi para pemalsu hadis;
4. Menjelaskan tingkah laku rawi-rawinya;
5. Meletakkan kaidah-kaidan untuk mengetahui hadis mauḍū’.
32 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 9_Syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi
A. Syarat-syarat Periwayatan
Secara umum seluruh umat Islam dapat meriwayatkan hadis, orang dewasa maupun
anak-anak. Namun, ulama berbeda pendapat dalam periwayatan hadis oleh anak-anak, sebab
faktor usia mereka yang belum balig untuk menyampaikan informasi, meskipun kita ketahui
bahwa anak-anak diusia dua tahun mempunyai pendengaran yang baik dalam menerima
informasi, serta dapat menirukan. Kendati demikian daya rekam yang mereka miliki tidak
cukup kuat untuk jangka lama, sehingga informasi yang pernah diperoleh tidak direproduksi
pada usia dewasa. Karena itu, penerimaan hadis harus dalam usia yang dapat merekam
informasi secara baik, dan dalam jangka waktu yang lama informasi itu tidak rusak karena
terlupakan.11
Menurut ‘Ajāj al-Khaṭīb, Ulama hadis pada umumnya mengakui kewenangan
pendengaran anak kecil –sebelum menginjak usia taklif–, ada tiga pendapat disebutkan
sebagai acuan kewenangan berikut. Usianya di atas 5 tahun (menginjak masa mumayyiz),
pendapat ini disebutkan oleh Imam al-Bukhārī dari riwayat sahabat Maḥmūd ibn Rabī’12,
yang menerima hadis saat berusia 5 tahun. Al-Ḥāfiẓ Mūsa ibn Hārūn mengatakan,
kewenangan diberikan kepada anak yang dapat membedakan antara anak sapi dan keledai,
perkataan Mungkin yang dimaksud adalah anak dalam usia tamyiz. Dimaksud tamyiz, yakni
yang dapat berdialog, dan umumnya anak yang berusia tamyiz mampu mendengar dengan
baik meskipun belum berusia 5 tahun. Ini termasuk pendapat ulama mutaqaddimin. Namun,
jika ada anak dalam usia tersebut belum mampu melakukan percakapan dengan baik, maka
periwayatannya tidak dapat diterima meskipun mereka telah berusia 5 tahun atau lebih.13
Tetapi, Ibn Wa’in menetapkan batas usia anak tersebut harus telah mencapai umur 15
tahun. Beliau mengajukan alasan hadis Ibn ‘Umar,14
Aku menghadap kepada Rasulullah saw. (untuk mengikuti perang) ketika perangUhud, saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau tidak memperkenankan aku.
11Zuhri, Hadis Nabi…, h. 109.12Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār at-Taṣīl, 2012), Juz.
I, hadis no. 78, h. 251.13Muhammad ‘Ajāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Fikr, 1979 M), h. 228-229.14Wahid, Studi…, h. 134.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 33
Kemudian aku menghadapnya lagi di hari perang Khandaq, dan saat itu aku telahberusia 15 tahun, beliau memperkenankan aku.15
Adapun syarat terpenuhinya suatu periwayatan adalah sebagai berikut:
1. Islam, maka periwayatan orang non muslim tidak dapat diterima. Berbeda halnya jika
orang tersebut memeluk Islam seperti periwayatan hadis Jubair ibn Muṭ’im. Berikut pula
riwayat orang fasik lebih dapat diterima apabila ia telah bertaubat dan diakui sebagai
orang yang adil, seperti yang dilakukan Ibnu Hajar dengan melakukan qiyas aulawi
terhadap periwayatan hadis Jubair yang mendengar hadis ketika masih kafir, dan
meriwayatkannya setelah memeluk Islam.16
2. Balig dan berakal sehat; terhadap periwayatan orang gila tetap tidak dapat diterima meski
ia telah sembuh dari penyakit gilanya. Karena sudah pasti ia tidak dapat mengingatnya
dalam keadaan kesadarannya telah hilang, sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai
orang yang ḍabit.
3. ‘Adalah. Sifat yang melekat pada seorang periwayat hadis dengan tidak melakukan dosa
kecil maupun besar dan sealau menjaga muru’ah, sehingga ia selalu setia terhadap Islam.
4. Ḍabiṭ. Teliti dan cermat, baik ketika menerima maupun menyampaikan hadis. Dengan
kata lain ia adalah orang yang memiliki hafalan yang kuat, pintar, dan tidak pelupa.17
Dhabit pada istilah, ialah penuh perhatian perawi kepada yang didengar diketika dia
menerimanya serta memahami apa yang didengar itu hingga ia menyampaikannya kepada
orang lain. Ḍabiṭ itu ada dua yaitu:
1. Ḍabiṭ ṣadr, yakni menghafal dengan baik,
2. Ḍabiṭ kitab, yakni memelihara kitabnya dari sisipan ataupun sebagainya.
Jalan mengetahui ke-ḍabiṭan seseorang ialah mengecek riwayatnya dengan riwayat orang
lain. Jika sesuai dengan riwayat orang lain maka riwayatnya diterima. Lebih dari itu,
perbedaan yang sesekali terjadi tidaklah menghalangi kita menerima riwayatnya, jika
banyak terjadi perbedaan dengan riwayat orang lain, tentulah riwayatnya tidak diterima.18
B. Metode Menerima Riwayat
Klasifikasi penerimaan riwayat dibagi kedalam 8 cara:
1. Sama’ min lafẓi asy-syaikh, mendengar atau meriwayat langsung dari perkataan
gurunya, baik secara lisan atau tulisan, yang diterima dengan didiktekan ataupun
15Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Mesir: Maktabah al-Ma’arif,t.t), hadis no. 2543, h. 433.
16Wahid, Studi…, h. 135.17Zuhri, Telaah Hadis…, h. 110.18Sohari sahrani, Ulumul hadits (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) h. 182.
34 | Triansyah Fisa, M.T.H.
melalui kitabnya. Metode ini dipandang paling bagus diantara metode yang lain.
Namun, alangkah baiknya jika dipadukan dengan mencatat dari setiap riwayat yang
diterima.
Adapun lafal yang digunakan dalam metode ini, berikut:
نا ي / أخ أخ Telah mengabarkan pada ku/kami
/ حدثنا حدث Telah memberitahukan pada ku/kami
سمعت / سمعنا Saya/kami telah mendengar
ي / أنبأنا أنبأ Telah menceritakan kepadaku/kami
/ قال لنا قال Telah berkata kepadaku/kami
/ ذكر نا ذكر Telah bertutur kepadaku/kami
2. Qira'ah (قراءة) disebut juga dengan istilah ‘arḍMaksudnya adalah seorang perawi mengajukan riwayat hadisnya kepada hadisnya
dengan cara perawi sendiri yang membacanya atau orang lain, sementara ia
mendengarkan. Lafal yang dipakai untuk periwayatan hadis dengan metode ini sebagai
berikut:
فالن قرئت ع Aku membacakan hadis di depan fulan
قر بھقرئ عليھ وأنا أسمع فأ Dibacakan (sebuah hadis) dihadapannya dan iamendengarnya dengan cermat
3. Ijāzah (إجازة)Seorang guru memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis
yang ada padanya, baik melalui lisan maupun tulisan. Adapun bentuknya dapat
dikelompokkan menjadi:
a. Guru memberikan rekomendasi hadis tertentu kepada orang tertentu, misalnya
dengan lafal زتك البخاري أج (aku memberikan rekomendasi ini kepada Bukhari)
b. Guru memberikan rekomendasi hadis tertentu kepada orang lain, seperti lafal أجزتك
ي مسموعا (aku memberikan rekomendasi hadis ini kepada mereka yang
mendengarkannya.
c. Guru memberikan rekomendasi hadis kepada orang umum, misalnya dengan lafal
أجزت املسلمون Aku memberikan rekomendasi hadis ini kapad kaummuslimin
فالن أجاز Seseorang telah memberikan izin kepadaku untukmeriwayatkan hadis.
حدثنا إجازة Telahmenyampaikan riwayat kepadaku dengan disertai izinuntuk meriwayatkan kembali.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 35
نا إجازة أخ Telah menceritakan kepadaku. Lafal ini sering dipakai olehulama hadis generasi akhir atau mutaakhkhirin.
d. Munāwalah (املناولة)Seorang guru memberikan manuskripnya kepada seseorang dengan disertai ijazah
atau memberikan manuskrip terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya
sekalipun tanpa ijazah. Hadis yang diperoleh dengan munawalah yang disertai
ijazah boleh diriwayatkan. Sedang yang tanpa ijzajah tidak diperbolehkan
(menurut pendapat yang sahih), lafal yang dipakai sebagai berikut:
ناول Seorang guru hadis telah memberikan manuskrip kepadaku
ي وأجاز ناول Seorang guru hadis telah memberikan manuskrip kepadakudisertai ijazah
Dua lafal di atas lebih baik daripada lafal-lafal berikut meskipun diperbolehkan
حدثنا مناولة Telah menyampaikan riwayat kepadaku secara munawalah
نا مناولة إجازة أخ Telah menyampaikan berita kepadaku secara munawalah disertaiijazah.
e. Kitābah/Mukātabah اتبة) (الكتابة / املSeorang muhaddis menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberitakan kepada
orang tertentu, baik ia menulis sendiri atau dituliskanoleh orang lain atas
permintaannya. Lafal yang digunakan dalam metode ini sebagai berikut:
فالن كتب إ Seorang guru hadis telah menulis sebuah hadis kepadaku
فالن كتابة حدث Telah menyampaikan riwayat kepadaku melalui koresponden
ي فالن كتابة أخ Telah menyampaikan berita kepada melalui koresponden
f. I‘lām ( ماإلعال )
Seorang guru memberitaukan kepada muridnya hadis atau kitab hadis yang telah
diterima dari perawinya. Dalam hal ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa
metode ini dianggap sah, meskipun sebagian kecil menganggapnya tidak sah.
Lafal yang dipakai adalah
بكذاأع شي لم Guruku telah memberitahukan riwayat hadis kepadaku
g. Waṣiyah (الوصية)
Seorang guru ketika akan meninggal dunia atau bepergian, memberi washiyah
sebuah manuskrip hadis yang diriwayatkannya kepada seseorang. Lafal yang
digunakan adalah
إ فالن بكذاأو Seseorang telah memberi wasiat kepadaku sebuah manuskrip
36 | Triansyah Fisa, M.T.H.
hadisnya
h. Wijadah (الوجادة)Seseorang yang tidak melalui cara sima‘ atau ijazah, menemukan manuskrip hadis
yang telah ditulis perawinya. Dalam hal ini, ulama mengkategorikan hadis-hadis
yang diperoleh dengan cara demikian sebagai hadis munqqati (terputus) walaupun
tertutup kemungkinan ada indikasi bersambung. Lafal-lafa yang digunakan adalah
وجدت بخط فالن Aku telah menemukan tulisan seorang guru hadis
قرأت بخط فالن بكذا Aku telah membaca hadis tulisan seorang guru
Disamping lafa-lafal periwayatan dalam metode tahammul wal-ada' tersebut, ada
kata-kata (harf) yang sering didapati dalam sanad, ‘an (عن) dan anna (أن ) yang berfungsi
sebagai petunjuk tentang cara periwayatan yang telah ditempuh oleh perawi, juga sebagai
bentuk persambungan matarantai sanad yang bersangkutan. Sebagian ulama berpendapat
bahwa hadis yang lafal periwayatnnya menggunakan ‘an dan anna itu sanadnya terputus, tapi
mayoritas ulama menilainya melalui sima‘, selama dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Dalam matarantai sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi (tadlis) yang
dilakukan perawi.
2. Antara perawi dengan perawi terdekat yang menggunakan harf ‘an atau anna itu
dimungkinkan terjadi pertemuan.
3. Malik bin Anas, Ibn ‘Abd al-Bar dan al-Iraqi menambahkan satu syarat lagi, yakni
para perawi harus orang-orang terpercaya.
C. Metode Menyampaikan Riwayat
Metode periwayatan hadis dilakukan dengan lafal dan ada pula dengan makna, berikut
uraiannya:
a. Periwayatan hadits dengan lafal (riwayat bil lafzi)
Meriwayatkan hadis dengan lafal adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafal yang
mereka terima dari Nabi Muahmmad. Dengan istilah lain yaitu meriwayatkan hadis dengan
lafal yang masih asli dari Nabi Muhammad saw.. Kebanyakan sahabat menempuh
periwayatan hadis melalui jalur ini. Mereka berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan
redaksi dari Nabi Muhammad saw. bukan menurut redaksi mereka. Malahan semua sahabat
menginginkan agar periwayatan itu dengan lafzi bukan maknawi.
Tercatat dalam sejarah, bahwa para sahabat nabi adalah orang yang sangat berhati-hati
dan ketat dalam periwayatan hadis. Mereka tidak mau meriwayatkan sebuah hadis hingga
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 37
yakin betul teks serat huruf demi huruf yang akan disampaikan itu sama dengan yang mereka
terima dari Nabi Muhammad saw..
Sebagian sahabat ada yang jika ditanya tentang sebuah hadis merasa lebih senang jika
sahabat lain yang menjawabnya. Hal demikian agar ia terhindar dari kesalahan periwayatan.
Menurut mereka, apabila hadis yang diriwayatkan itu tidak sesuai dengan redaksi yang
diterima, mereka telah melakukan perbuatan dosa, seolah-olah telah melakukan pendustaan
terhadap nabi Muhammad saw.. Kekhawatiran tersebut karena didorong oleh rasa keimanan
mereka yang kuat kepada Nabi Muhammad saw. .
Dalam hal ini Umar bin Khatab pernah berkata:
.من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلمSiapa yang mendengar sebuah hadis kemudian ia meriwayatkannya seperti yang ia dengar,maka ia telah selamat.
Periwayatan dengan lafal ini dapat kita lihat pada hadis-hadis yang memiliki redaksi
sebagai berikut:
Pertama:. سمعت (Saya mendengar) Contoh:
عن المغيرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد )( رواه مسلم وغيره النار فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
Dari Mughirah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnyadusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain. Maka siapa berdusta atasnamaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR.Muslim dan lain-lainnya)
Kedua. حدثنى ( ia menceritakan kepadaku) Contoh:
سول الله حدتنى مالك عن ابن شهاب عن حميدبن عبد الرحمن عن ابى هريرة رضي الله عنه ان ر.ما تقدم من ذنبه عليه وسلم قال : من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر لهصلى الله
Malik dari Ibnu Syihab telah bercerita kepadaku, dari Humaidi bin Abdur Rahman dari AbiHurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang melakukan qiyam Ramadhandengan iman dan ihtisab, diampuni doasa-dosanya yang telah lalu.
Tiga: أخبرنى (Ia memberitakan kepadaku)
Empat: رأيت (Saya melihat) Contoh:
نى ويقول إ” يعنى األسود “ عن عباس بن ربيع قال : رأيت عمربن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ( رواه قبلك ما قبلتك الء علم أنك حجر التضر وال تنفع ولوال أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي
)البخارى ومسلم Dari Abbas bin Rabi’ ra., ia berkata: Aku melihat Umar bin Khaththab ra., mencium HajarAswad lalu ia berkata: “Sesungguhnya benar-benar aku tahu bahwa engkau itu sebuah batu
38 | Triansyah Fisa, M.T.H.
yang tidak memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat. Seandainya aku tidakmelihat Rasulullah saw.. menciummu, aku (pun) tak akan menciummu.” (HR. Bukhari danMuslim)
Hadis yang menggunakan lafal-lafal di atas memberikan indikasi, bahwa para sahabat
langsung bertemu dengan Nabi saw. dalam meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu para ulama
menetapkan periwayatan hadis dengan lafal dapat dijadikan hujjah, dan tidak ada khilaf.
b. Periwayatan dengan makna (riwayat bil ma‘na)
Meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis berdasarkan
kesesuaian maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang
meriwayatkan. Dengan kata lain apa yang diucapkan oleh Rasulullah hanya dipahami
maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafal atau susunan redaksi mereka
sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat dan ada
pula yang lemah. Di samping itu kemungkinan masanya sudah lama, sehingga yang masih
ingat hanya maksudnya sementara apa yang diucapkan Nabi sudah tidak diingatnya lagi.
Periwayatan hadis dengan makna tidak diperbolehkan kecuali jika perawi lupa akan lafal tapi
ingat akan makna, maka ia boleh meriwayatkan hadis dengan makna.
Sedangkan periwayatan hadis dengan makna menurut Luis Ma’luf adalah proses
penyampaian hadis-hadis Rasulullah saw. dengan mengemukakan makna atau maksud yang
dikandung oleh lafal karena kata makna mengandung arti maksud dari sesuatu .
Menukil atau meriwayatkan hadis secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadis-
hadis belum terkodifikasi. Adapun hadis-hadis yang sudah terhimpun dan dibukukan dalam
kitab-kitab tertentu (seperti sekarang), tidak diperbolehkan merubahnya dengan lafal/matan
yang lain meskipun maknanya tetap.
Dengan kata lain bahwa perbedaan sehubungan dengan periwayatan hadis dengan
makna itu hanya terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadis. Setelah
hadis dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu telah hilang dan
periwayatan hadis harus mengikuti lafal yang tertulis dalam kitab-kitab itu, karena tidak perlu
lagi menerima hadis dengan makna.
Pada umumnya para sahabat Nabi membolehkan periwayatan hadis secara makna,
seperti: Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas‘ud (wafat 32 H/652 M),
Anas bin Malik (wafat 93 H/711 M), Abu Darda’ (wafat 32 H/652 M), Abu Hurairah (wafat
58 H/678 M) dan Aisyah istri Rasulullah (wafat 58 H/678 M). Para sahabat Nabi yang
melarang periwayatan hadis secara makna, seperti: Umar bin al-Khaṭṭab, Abdullah bin Umar
bin al-Khaṭṭab dan Zaid bin Arqam.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 39
Terjadinya periwayatan secara lafal disebabkan beberapa faktor berikut:
1. Adanya hadis-hadis yang memang tidak mungkin diriwayatkan secara lafal, karena tidak
adanya redaksi langsung dari nabi Muhammad saw., seperti hadis fi‘liyah, hadis
taqririyah, hadis mauquf dan hadis maqthu‘. Periwayatan hadis-hadis tersebut adalah
secara makna dengan menggunakan redaksi perawi sendiri.
2. Adanya larangan nabi untuk menuliskan selain Alquran. Larangan ini membuat sahabat
harus menghilangkan tulisan-tulisan hadis. Di samping larangan, ada pemberitahuan dari
nabi tentang kebolehan menulis hadis
3. Sifat dasar manusia yang pelupa dan senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu
yang dipahami lebih mudah dari pada mengingat susunan kata-katanya.
Adapun contoh hadis maknawi adalah sebagai berikut:
Ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw., yang bermaksud menyerahkan dirinya(untuk dikawin) kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah,nikahkanlah wanita tersebut kepadaku, sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatuuntuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagian ayat-ayat Alquran. Maka Nabisaw. berkata kepada laki-laki tersebut: Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut denganmahar (mas kawin) berupa mengajarkan ayat Alquran.19
Dalam satu riwayat disebutkan:
“Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar berupa (mengajarkan) ayat-ayat Alquran.”Riwayat lain menyebutkan:
“Aku kawinkan engkau kepada wanita tersebut atas dasar mahar berupa (mengajarkan)ayat-ayat Alquran.”riwayat yang lainnya jug menyebutkan:
“Aku jadikan wanita tersebut milik engkau dengan mahar berupa (mengajarkan) ayat-ayatAlquran.” (Al-Hadis)
c. Hukum Periwayatan Hadis secara Makna
19Muḥammad Muḥammad Abu Syuhbah, Dafa‘ ‘an as-Sunnah (Libanon: Majma‘ al-Buḥūṡ al-Islamiyah, 1985), h. 69.
40 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Telah terjadi perselisihan pendapat antara ulama tentang hukum periwayatan hadis
secara makna. Perselisihan itu terjadi sebelum dikodifikasinya hadis. Sedangkan setelah
pentadwinan dengan berbagai karangan-karangan buku hadis maka tidak boleh adanya
periwayatan hadis secara makna.
Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa meriwayatkan hadis dengan maknanya
itu sebagai berikut:
1. Tidak diperbolehkan, pendapat segolongan ahli hadis, ahli fiqh dan ushuliyyin.
2. Diperbolehkan, dengan syarat yang diriwayatkan itu bukan hadis marfu‘.
3. Diperbolehkan, baik hadis itu marfu‘ atau bukan asal diyakini bahwa hadis itu tidak
menyalahi lafal yang didengar, dalam arti pengertian dan maksud hads itu dapat
mencakup dan tidak menyalahi.
4. Diperbolehkan, bagi para perawi yang tidak ingat lagi lafal asli yang ia dengar, kalau
masih ingat maka tidak diperbolehkan menggantinya.
5. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu yang terpenting adalah isi, maksud
kandungan dan pengertiannya, masalah lafal tidak jadi persoalan. Jadi diperbolehkan
mengganti lafal dengan sinonimnya.
6. Jika hadis itu tidak mengenai masalah ibadah atau yang diibadati, umpamanya hadis
mengenai ilmu dan sebagainya, maka diperbolehkan dengan catatan:
a. Hanya pada periode sahabat
b. Bukan hadis yang sudah didewankan atau di bukukan
c. Tidak pada lafal yang diibadati, umpamanya tentang lafal tasyahud dan qunut.
d. Syarat–syarat Periwayatan Secara Makna
Pendapat yang populer di kalangan ulama hadis menyatakan selain sahabat diperkenankan
meriwayatkan hadis secara makna dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab. Dengan demikian periwayatan matan hadis akan
terhindar dari kekeliruan.
2. Periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa misalnya karena lupa susunan
secara lafal atau harfiah.
3. Yang diriwayatkan dengan makna bukan merupakan bentuk bacaan bacaan yang sifatnya
ta’abbudi, seperti zikir, doa, azan, takbir dan syahadat, serta bukan yang berbentuk
jawami al kalim.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 41
4. Periwayat hadis secara makna atau mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang
diriwayatkannya agar menambah kata اوكما قال atau او نحو هدا atau yang semakna dengannya
setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.
5. Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum
dibukukannya hadis secara resmi. Sesudah masa pembukuan (kodifikasi) hadis,
periwayatan hadis harus secara lafal.
Para sahabat lainnya berpendapat bahwa dalam keadaan darurat karena tidak hafal
persis seperti yang di wurud-kan Rasulullah saw., dibolehkan meriwayatkan hadis secara
maknawi. Periwayatan maknawi artinya periwayatan hadis yang matannya tidak sama dengan
yang didengarnya dari Rasulullah saw., tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh
sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw..
Shubhi Ismail menyebut empat syarat yang harus dipenuhi periwayatan dengan makna
adalah pertama, perawi hadis itu betul-betul seorang yang alim mengenai ilmu nahwu, sharf
dan ilmu bahasa Arab; kedua, perawi itu harus mengenal dengan baik segala madlul lafal dan
maksud-maksudnya; ketiga, perawi itu harus betul-betul mengetahui hal-hal yang berbeda di
antara lafal-lafal tersebut; dan keempat, perawi itu harus mempunyai kemampuan
menyampaikan hadis dengan penyampaian yang benar dan jauh dari kesalahan atau
kekeliruan.
Di samping empat syarat tersebut Abu Rayyah menambah satu syarat lagi, yaitu tidak
boleh penambahan atau pengurangan di dalam terjemahan (penyampaian hadis dengan
makna) terserbut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh
meriwayatkan hadis bil ma‘na, tetapi boleh meriwayatkan bi al-lafzh.
D. Kedudukan Riwayat Mu‘an ‘an dan Mu‘annan
Seorang periwayat yang meriwayatkan hadis dengan lafal ‘an, maka hadis itu disebut
dengan mu‘an ‘an. Adapun periwayatnya disebut dengan mu‘an ‘in. jika seorang periwayat
meriwayatkan hadis dengan lafal ‘anna, maka hadisnya disebut mu‘annan dan ia disebut
mu‘annin.
Hadis yang diriwayatkan dengan cara tersebut dapat dihukumkan muttaṣil dengan
memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut al-Bukhāri dan Ibn al-Madini, syaratnya adalah:
a. Periwayatnya bukan seorang mudallis,
b. Periwayatnya harus pernah berjumpa dengan guru yang hadisnya ia riwayatkan,
42 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Periwayatan ini dikenal dalam literatur ilmu hadis dengan “isytirath ahnu‘asharah”.
Menurut sebagian lainnya poeriwayat harus diketahui dengan yakin, bahwa ia benar-benar
menerima hadis tersebut dari gurunya.20
20Wahid, Studi…, h. 142.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 43
Topik 10_ Definisi dan fungsi Ilmu Rijalil Hadis
A. Pengertian Ilmu Rijal Hadis
Secara bahasa rijāl adalah kaum laki-laki21, namun dalam keilmuan hadis, rijāl
digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan para perawi hadis (orang-orang yang
meriwayatkan hadis Nabi saw.). Penggunaan istilah ini untuk membicarakan tentang tokoh-
tokoh yang membawa hadis dari Nabi saw. hingga periwayat terakhir. Secara istilah ilmu rijāl
al-ḥadīṡ dapat dipahami sebagai berikut:
Ilmu untuk mengetahi keadaan para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagaiperiwayat hadis.22
Pengertian ini menunjukkan bahwa pembahasan ilmu ini mencakup seluruh periwayat
hadis baik itu sahabat Nabi, tabiin dan generasi setelah mereka. Sementara fokus
pembahasannya hanya keadaan mereka dalam menerima dan meriwayatkan hadis, dimulai
dari sejarah kehidupan (dari masa lahir hingga wafat), negeri asal, negeri pengembaraan serta
guru-guru dan murid-muridnya.
B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan
Kemunculan ilmu Rijāl al-Ḥadīṡ merupakan kontruksi dari berkembang dan
menyebarnya penggunaan sanad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Sanad telah ada
sejak sahabat Rasulullah saw. dimulai dari sikap kehati-hatian mereka terhadap berita yang
datang, sebagaimana riwayat Abu Bakr aṣ-Ṣiddīq dalam kisah ketika seorang nenek datang
meminta bagian warisan23, kemudian kisah ‘Umar bin al-Khaṭṭab dalam peristiwa isti'żān
(minta izinnya) Abu Musa24, juga kisah taṡabbut (klarifikasi) ‘Ali bin Abu Ṭālib ketika beliau
meminta bersumpah bagi orang yang menyampaikan hadis Rasulullah saw. kepadanya.25
Hanya saja makin banyaknya pertanyaan terhadap sanad maka semakin intens pula
orang meneliti dan memeriksa sanad, hal ini dimulai setelah terjadinya fitnah ‘Abdullāh bin
21Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,2002), h. 479.
22Muhammad Adib Ṣaliḥ, Lamahat fī Uṣūl al-Ḥadīṡ (Beirut: Maktabah Islami, 1399 H), h. 74.23Syamsud-dīn aż-Żahabī, Tażkirah al-Ḥufāẓ (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1998), juz. 1, h. 9. Telah
di takhrij oleh Imam Mālik bin Anas, Muwaṭṭa' al-Imām Mālik (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-‘Arabī, 1985), juz.2, h. 513. Abī Dāud Sulaimān bin al-Asy‘aṡ as-Sijistānī, Sunan Abī Dāud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), juz. 3,no. 2894, h. 213. Juga Sunan Ibnu Majah, Sunan at-Tirmiżī, Sunan an-Nasā'ī, dan al-Mu‘jam al-Kabīr liṭ-Ṭabrānī.
24Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār at-Tāṣīl, 2012), hadis no. 6251, Juz. 8, h. 151. Muslim,Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hadis no. 2153, h. 1081.
25Abū Bakr Aḥmad al-Jarjānī, al-Mu‘jam fī Asāmī Syuyūkh Abī Bakr (Madinah: Maktabah al-‘Ulumwal-Hikam, 1990), juz. 2, h. 697.
44 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Saba dan pengikut-pengikutnya di akhir kekhalifaan Uṡman bin ‘Affān. Penggunaan sanad
terus berlangsung dan bertambah seiring dengan menyebarnya para asḥabul-ahwā (pengikut
hawa nafsu) di tengah-tengah kaum muslimin, juga banyaknya fitnah yang mengusung
kebohongan sehingga orang-orang tidak mau menerima hadis tanpa sanad agar mereka dapat
mengetahui perawi-perawi hadis tersebut dan mengenali keadaan mereka.
Setiap berkembangnya zaman, maka semakin banyak dan panjang jumlah perawi
dalam sanad. Untuk itu perlu dijelaskan keadaan perawi tersebut dan memisah-misahkannya,
apalagi dengan munculnya bid‘ah-bid‘ah dan hawa nafsu serta banyaknya pelaku dan
pengusungnya. Karena itu tumbuhlah ilmu Rijāl al-Ḥadīṡ yang merupakan suatu
keistimewaan umat ini di hadapan umat-umat lainnya.
Ulama yang pertama kali memperkenalkan dan mempelajari secara serius adalah
Imam al-Bukhāri (w. 256 H), salah satu kitabnya yang membahas tentang ini adalah al-Kuna.
Kemudian, usaha itu dilaksanakan juga oleh Muḥammad bin Sa‘ad (w. 230 H) dengan
kitabnya Ṭabāqat al-Kabīr.26 Setelah itu kajian ini terus berkembang dengan ditemukannya
karya Ibn ‘Abdil-Bar (w. 463 H), al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Aṣḥāb.27
Selanjutnya, ‘Izzud-Din bin al-Aṡir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul-Aṡir
(w. 630 H), ulama abad ketujuh hijriah ini melanjutkan usaha tersebut dengan mengumpulkan
kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya dan berhasil menyusun kitab Usūd al-Gābah fī
Ma‘rifah aṣ-Ṣaḥābah. Kitab ini memuat uraian tentang para sahabat Nabi saw. Atau rijal al-
hadis pada ṭabāqat (generasi) pertama, meskipun didalamnya terdapat nama-nama yang
bukan sahabat. Ibnul-Atsir ini adalah saudara dari Majduddin bin al-Aṡir pengarang an-
Nihāyah fī Garībil-Ḥadīṡ. Berikutnya muncul pula karya ‘Izzud-Din yang selanjutnya dan
direvisi oleh aż-Żahabī (w. 747 H) dalam kitab at-Tajrid.28
Pada abad ke-10 H, al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar datang dengan mengusung kitab al-Iṣābah
dengan memuat informasi dari kitab al-Istī‘āb, Usud al-Gābah dan informasi tambahan diluar
kedua kitab tersebut. Selanjutnya kitab Ibnu Ḥajar tersebut diringkas kembali oleh as-Suyuṭi
dalam kitab ‘Ainul Iṣābah.29
C. Objek Ilmu Rijāl al-ḤadīṡIlmu Rijāl al-Ḥadīṡ dibagi menjadi dua cabang ilmu tersendiri, yaitu Tārīkh ar-
Ruwah, dan al-Jarḥ wa at-Ta‘dil. Ilmu Tārīkh ar-Ruwah hanya sebatas memahami keadaan
26Ṣaliḥ, Lamahat…, h. 73.27Zuhri, Telaah Hadis…, h. 118.28Ramli Abdul Wahid, Ilmu-Ilmu Hadis (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 3. Lihat juga,
Zuhri, Telaah Hadis…, h. 119.29Ṣaliḥ, Lamahat…, h. 75.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 45
atau keberlangsungan seorang perawi dalam kurun waktu penerimaan dan periwayatannya
[seperti sejarah ringkas riwayat hidup perawi, mazhab yang dipeganginya, dan keadaan para
perawi itu dalam menerima hadis serta keadaan pribadinya],30 sedang penentuan seorang
perawi itu baik atau tidak dan kredibilitasnya sebagai seorang perawi, penghakiman itu
dilakukan saat penelitian jarh wa ta‘dil si perawi, jarh melihat sisi buruknya dan ta‘dil
melihat sisi baiknya.31 Penentuan itu dilakukan dengan mengikuti beberapa kaidah yang
disepakati ulama agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan demikian masing-masing keilmuan
tersebut memiliki pre-posisinya tersendiri.
Ilmu hadis ini sangat penting, karena ruang lingkup ilmu hadis mencakup kajian
terhadap sanad dan matan. Namun, yang menjadi fokus kajian ilmu Rijāl al-Ḥadīṡ ini hanya
para perawi hadis yang membentuk sanad, yaitu orang-orang yang terkait dengan periwayatan
hadis, baik ia seorang guru, murid, atau mukharrij.32 Tidak heran apabila para ulama
memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu ini.33
D. Tujuan dan Faedah
Pertimbangan utama dalam mempelajari ilmu ini karena ia menyangkut validitas dan
kredibilitas seorang perawi dalam meriwayatkan pesan Nabi saw. Disamping untuk
mengetahui kebersambungan (muttasil) atau tidak suatu sanad hadis. Maksud persambungan
di sini adalah petemuan langsung antara perawi (penerima berita) itu dengan gurunya
(pembawa berita) atau hanya sebatas pengakuan saja. Kesemuanya itu dapat diketahui melalui
ilmu ini. Ketersambungan sanad ini menjadi salah satu syarat kesahihan sebuah hadis dari
segi sanad [Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat]. Perhatian para ulama terhadap
ilmu ini sangat besar dengan maksud ingin mengetahui para perawi dan meneliti keadaan
mereka, sejauhmana dapat diterima hadis yang mereka sampaikan. Muhammad bin Sirin
pernah mengatakan : "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu
mengambil agamamu"34
Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan kajian hadis. Hal ini dilandasi
bahwa obejk kajian hadis pada dasarnya terkait dalam dua hal, yakni sanad dan matan.
30al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 253.31al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 260.32Ulama mutaqaddimin menyebutkan pembahasan ilmu ini kedalam ilmu Tarikh ar-Ruwat atau ilmu at-
Tarikh atau wafayat ar-Ruwat, ada juga yang menamakan karyanya dengan at-Tawarikh wa al-Wafayat, karenamereka sering menyebut istilah-istilah tersebut dalam buku-buku Ulumul Hadis dan Musthalahnya. Merekamengkhususkan karya-karya mereka yang berkaitan dengan itu dengan nama yang merujuk kepadanya.
33al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 253.34Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim
46 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Dengan hadirnya ilmu ini akan sangat membantu untuk mengetahui derajat hadis dan sanad
(apakah sanadnya muttaṣil atau munqaṭi').
Imam as-Sakhawi mengatakan, “faidah ilmu ini adalah dapat diketahui keamanan dari
bercampurnya al-mutasyabbihin (para rijal hadis yang memiliki kesamaan); seperti yang
memiliki kesamaan namanya atau kuniyahnya [nama panggilan dari daerah kelahiran] atau
yang lain, kita dapat juga menelaah terjadinya tadlis [penyembunyian] secara jelas dan
menyingkap hakikat an’anah [periwayatan dengan menggunakan lafal ‘an] untuk mengetahui
hadis yang mursal atau munqaṭi' dan membedakannya dari yang musnad”.
E. Ulama dan Kitab Yang Dipergunakan Dalam Penelitian Hadis
Kitab yang disusun untuk membahas ilmu ini sanat beragam, ada yang hanya
menerangkan secara ringkas dari para sahabat saja, ada yang menyusunnya berdasarkan
tingkatan tabaqat atau generasi demi generasi. Ada juga yang menyusun berdasarkan tahun
wafat seorang perawi, lalu menyebut biografinya dan berita-berita lain tentang perawi itu.
Berikut beberapa kitab yang berkenaan dengan ilmu Rijāl al-Ḥadīṡ;
1. Kitab Ma'rifat Man Nazala minash-Shahabah Sa'iral-Buldan, karya Imam Ali bin
Abdillah Al- Madini (wafat tahun 234 H). Kitab ini tidak sampai kepada kita.
2. Kitab Tarikh Ash-Shahabah, karya Muhammad bin Isma'il Al- Bukhari (wafat tahun
245 H). Kitab ini juga tidak sampai kepada kita.
3. Al-Isti'ab fii Ma'rifaatil-Ashhaab, karya Abu 'Umar bin Yusuf bin Abdillah yang
masyhur dengan nama Ibnu 'Abdil-Barr Al-Qurthubi (wafat tahun 463 H). dan telah
dicetak berulang kali, di dalamnya terdapat 4.225 biografi shahabat pria maupun
wanita.
4. Ushuudul-Ghabah fii Ma'rifati Ash-Shahabah, karya 'Izzuddin Bul-Hasan Ali bin
Muhammad bin Al-Atsir Al-Jazari (wafat tahun 630 H), dicetak, di dalamnya
terdapat.7554 biografi.
5. Tajrid Asmaa' Ash-Shahabah, karya Al-Hafidh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad
bin Ahmad Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H), telah dicetak di India.
6. Al-Ishaabah fii Tamyiizi Ash- Shahaabah, karya Syaikhul-Islam Al-Imam Al-Hafidh
Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Kinani, yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar Al-
'Asqalani (wafat tahun 852 H). Dan dia adalah orang yang paling banyak melalukan
pengumpulan dan penulisan. Jumlah kumpulan biografi yang terdapat dalam Al-
Ishaabah adalah 122.798 , termasuk dengan pengulangan, karena ada perbedaan pada
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 47
nama shahabat atau ketenarannya dengan kunyah- nya, gelar, atau semacamnya; dan
termasuk pula mereka yang disebut shahabat, namun ternyata bukan.
48 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Topik 11_Definisi dan fungsi Ilmu Jarh wa Ta’dil
A. Pengertian Jarh wa Ta’dilAl-jarḥ merupakan masdar dari kata jaraḥa – yajraḥu, secara bahasa diartikan “melukai”35
(membuat luka atau menyakiti (hati)36 yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu
atau luka dalam bentuk nonfisik seperti luka hati)37. Dalam peradilan, bila dikatakan jaraḥ al-
ḥākim asy-syāhid maksudnya “hakim melontarkan sesuatu yang menjatuhkan saksi (sifat
adilnya)”38 atau “menggugurkan keadilan saksi”.39 Secara istilah al-Khaṭīb menjelaskan, al-
jarḥ adalah
.ردهاو أو خيل حبفطه وضبطه مما يرتتب عليه سقوط روايته أو ضعفها تهعدالثلمييظهور وصف يف الرو Munculnya suatu sifat dalam diri seorang perawi yang dapat menodai keadilannya
atau yang mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, sehingga mengakibatkan gugur atau
lemah riwayatnya dan bahkan tertolak. Sedang at-tajrīḥ yaitu yang menyifatkan seorang
perawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan riwayatnya atau meniadakan
penerimaannya.40
Dalam definisi yang lain, al-Jazirī menyebutkan:
لراوي والشاهد سقط االعتبار بقوله ، وبطل العمل به .اجلرح : وصف مىت التحق Al-jarḥ adalah suatu sifat yang terdapat (melekat) pada periwayat hadis atau saksi,
perkataannya tidak dapat dipegangi, dan batal beramal dengannya.41 Dari kedua definisi
tersebut jelas yang dimaksudkan dengan jarḥ adalah sifat-sifat buruk pada perawi yang
menyebabkan hadisnya tidak dapat diterima.
At-ta‘dīl asal kata dari ‘adala masdarnya ‘addala artinya “meluruskan”, yakni
menjadikan seseorang benar atau baik, merupakan lawan dari buruk atau dengan kata lain
mensifatkan seseorang dengan sifat-sifat baik (adil) yang dimilikinya. Secara istilah, ‘adil
ialah orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaannya dan keriwayatannya.
Sehingga, khabar dan kesaksiannya dapat diterima.42
Ta‘dil secara istilah ialah
35Munawwir, al-Munawwir…, h. 180.36Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 881.37Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr al-Afriqī, Lisan al-`Arabi (al-Qahirah: Dār al-Ma`ārif, t.t.), jilid
2, h. 586.38al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 260.39Abu Lubabah Husain, al-Jarh wa at-Ta`dil (Riyad: Dār al-Liwa’, 1974 M), h. 19.40Al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 260.41Al-Jazirī ibnu al-Aṡīr, Jāmi` al-Uṣūl fi Aḥādīs ar-Rasūl (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid 1, h. 126.42Al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 260.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 49
فتظهر عدالته ويقبل خربهةوصف الراوى بصفات تزكي“Yang mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat membersihkannya (dari keburukan),
sehingga tampak sifat adilnya dan diterimalah khabarnya.”43
Sehingga definisi ilmu jarḥ wa at-ta’dil dapat dikatakan ilmu yang membahas hal ihwal
(keadaan) perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.44 Yang menunjukkan
bahwa pentingya mempelajari ilmu ini, hingga dapat dibedakannya antara yang sahih dengan
yang cacat, yang diterima dengan yang ditolak, dan dapat mengetahui sahih atau tidaknya
sebuah Hadis.
B. Dalil Disyariatkan al-Jarḥ wa at-Ta’dil
Kaidah-kaidah umum syari’at menunjukkan kewajiban memelihara sunah. Dengan
menjelaskan perihal keadaan para perawinya merupakan sarana yang lurus untuk menjaga
sunah. Dalil yang menjadi disyariatkannya al-jarḥ wa at-ta’dil adalah firman Allah Swt.
dalam surat al-Hujarat ayat 6:45
يها الذ ين امنوا ان جاء كم فا سق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم ند مني.“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatuberita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibahkepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesalatas perbuatanmu itu.”
Dalam surah al-Baqarah ayat 282, Allah Swt. juga menyebutkan:
نفرجلرجلنييكوملفإنرجالكممنشهيدين...واستشهدوا إحدامهاتضلأنالشهداءمنترضونممنوامرأدعوا...ماإذاالشهداءبوالاألخرىإحدامهافتذكر
”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jikatak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan darisaksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagimengingatkannya”.
Maksud kata “saksi-saksi yang kamu ridai” adalah orang yang di ridai agama dan
kejujurannya, yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi.46 Pengutipan dan
periwayatan hadis tidak kurang dari kesaksian itu, yang berarti hadis tidak diterima kecuali
dari orang-orang yang ṡiqah.47
43Al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 26144Ibid.45Ibid., h. 261.46Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur´ān al-`Aḍīm (Qāhirah: Mu´assasah Qurṭubah, 1421 H/2000 M), jilid 2, h.
508.47Al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 261
50 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Berkenaan dengan al-jarḥ, Rasulullah saw. bersabda:
العشرية.ئس أخوب“Seburuk-buruk saudara adalah dia”.48
Yang berkenaan dengan ta’dil, Rasulullah bersabda:
نعم عبد هللا خالد ابن الوليد سيف من سيوف هللا.”Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin al-Walid, sebilah pedang dari pedang-pedang
Allah.”49
C. Lafal-lafal yang dipergunakan dalam al-Jarḥ wa at-Ta’dil
Ungkapan yang digunakan dalam tajrih dan ta’dil menunjukkan kedudukan perawi
dalam tingkatan jarh dan ta’dilnya. Perihal penyebutan tingkatan ini para ulama berbeda
pendapat dalam menyusun tingkatan-tingkatannya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu as-Salah, dan Imam
an-Nawawi mengatakan ada 4 tingkatan, az-Zahabi dan al-’Iraqi menjadikannya 5 tingkatan,
sedang Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan.50 Namun, dari beberapa literatur
menyebutkan tingkatan jarh dan ta’dil dibagi menjadi enam tingkatan.51 Tingkatan ta’dil
disusun dari atas ke bawah, yakni dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah, sedang
tingkatan tajrih disusun dari bawah ke atas. Adapun tingkatan-tingkatannya adalah sebagai
berikut:
a. Tingkatan Ta’dil
Tingkatan tertinggi/pertama; penyifatan perawi dengan lafal mubalagah
(berlebih-lebihan) dengan bentuk af’al at-tafḍil atau lafal-lafal yang lain dengan
pengertian yang sejenisnya, seperti:52
ال أحد أفضال منه ؛ ثقة فوق ثقة؛ والثبتإليه املنتهى يف الضبطثق الناس؛ أثبت الناس حفظا وعدالة؛ أو .عنهيسألال؛ ال أعرف له نظريا يف عدلته وضبطهأضبط الناس؛ ليس له نظري؛ ؛ يف احلفظ والتثبت
Perawi dengan lafal-lafal ini seperti; Ibrahim bin Maisarah at-Ta´ibi, Jābir bin Yazid
(Abu Yazid al-Kūfī), al-Hasan bin Muhammad, ‘Abdullāh bin Yūsuf at-Tanisi, Ja’dah
al-Makhjumi, al-Ḥāriṡ bin Yazīd al-’Akalī, dan lain-lain.
48Muḥammad bin Ismā`īl Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr, t.t.), juz. 3, h. 1233.49Muḥammad bin `Īsa at-Tirmiżī, Sunan at-Tirmiżī (Beirut: Dār Iḥyā´ at-Turāṡ al-`Arabī, t.t.), juz. 2, no.
3846, h. 974.; Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal (Beirut: Dār Iḥyā´ at-Turāṡ al-`Arabī, t.t.), juz. 1,no. 1753, h. 498.
50Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadis (Bandung: PT Alma’arif, 1974), h. 313.51Al-Khaṭīb, Uṣūl…, h. 275-277.52Ibid., h. 275.; Rahman, Ikhtisar…, h. 314-316.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 51
Tingkatan kedua; penyifatan perawi dengan lafal penunjukkan kuatnya
kepercayaan seorang perawi kepada periwayat dengan pengulangan sifat yang sama
atau sepadan, seperti:53
؛ حجةثقة جافظ؛ ثقة ثقة؛ حجة حجة؛ ثقة حافظ؛ ثقة مأمون؛ ثبت ثقة؛ ضابط متقن؛ ثبت ثبت.حديثصاحب؛ ثبت حجة
Perawi dengan lafal-lafal ini seperti; Hafṣ bin ‘Umar al-Ḥāriṡ, Sulaimān bin Mugīrah,
Aḥmad bin Sa’īd, Ibrāhīm bin Sulaimān, Ibrāhīm bin Yūsuf, Ismā’īl bin Sālim al-
Asadī, dan lain-lain.
Tingkatan ketiga: penyifatan perawi dengan lafal yang menunjukkan
kepercayaan dan mengandung arti kuat ingatannya, seperti:
.م؛ ضابطإما؛ متقن؛ حافظ؛ حجة؛ ثبت؛ ثقةPerawi dengan lafal-lafal ini seperti; Aḥmad bin Sa’id bin Ibrāhīm, Juraij bin Uṡmān,
Zuhair bin Mu’awiyah, Qurrah bin Khalid as-Sadusi, Yaḥya bin Sa’īd, dan lain-lain.
Tingkatan keempat: penyifatan perawi yang menunjukkan kebaikan
keadaannya tanpa menunjukkan kekokohan ingatannya, seperti:
س به؛ مأمون؛صدوق سبليس ؛ال .خيار الناس؛ ه Perawi dengan lafal ini seperti; Muhammad bin Isḥāq, Sahl bin Uṡmān, Aḥmad bin
Ibrāhīm, Aḥmad bin al-Azhar, Aḥmad bin Āṣim, al-Jarh bin Makhlad al-’Ajli, al-
Ḥusīn bin Wāqad al-Marwazi, dan lain-lain.
Tingkatan kelima: penyifatan perawi yang menunjukkan kejujuran perawi, tapi
tidak menggambarkan hafalan dan kecermatannya, seperti:
.؛ صدوق يهمحمله الصدق؛ جيد احلديث؛ صاحل احلديث؛ مقارب احلديثPerwai dengan lafal-lafal ini seperti; Ibrahim bin al-’Abbas,
Tingkatan keenam: penyifatan perawi dengan sifat yang tidak menunjukkan
keḍabitan dan tidak pula menunjukkan sifat benar dan amanah, yakni lafal ta’dil yang
tidak mutlak melainkan pengaitan lafal pengharapan dalam bentuk tasgir (pengecilan
arti), seperti:54
س به؛ مقبول حدسثه؛ يروي شيخ؛ ليس ببعيد من الصواب صويلح؛ صدوق إنشاء هللا؛ أرجو أنه ال حديثه.
53Ibid., h. 276.54Ibid.
52 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Para ulama menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi dengan lafal pada
tingkat pertama sampai keempat. Sementara perawi yang termasuk dalam dua
golongan terakhir ini mendekati jarh, tidak dijadikan hujjah dan tidak ditulis hadisnya
kecuali untuk memberi contoh atau i’tibar ketika meneliti jalan hadis yang tunggal
agar dikethui apakah hadis itu memiliki mutabi’ (pendukung) atau tidak.
b. Tingkatan Tajriḥ55
Tingkat pertama: penyifatan perawi yang menunjukkan hanya sekedar daif
atau tidak bisa dijadikan pegangan, tapi mendekati sifat adil, seperti:
لعمدة؛ ليس حبجة؛ ال نعرفه منه وننكر ـفالن فيه مق؛ يف حديثه ضعف؛ فيه ضعف؛ لني احلديث ؛ ليس ؛ أوثق منه.سيء احلفظ؛ فيه خلف تكلموا فيه؛ ليس مرضيا؛ يهطعان ف
Tingkat kedua: penyifatan perawi dengan kelemahan yang lebih tinggi atau
menunjukkan sesuatu yang harus ditinggalkan, seperti:
ال حيتج ؛ديثمضطرب احل؛ روي ملا ينكر عليه؛ حديثه منكر؛ ضعيف احلديث؛ منكر احلديثضعفوه؛ .به
Perawi yang temasuk dalam dua tingkatan ini mendekati derajat ta’dil. Hadis
mereka diriwayatkan sebagai i’tibar dan tidak dijadikan hujah.
Tingkat ketiga: penyifatan perawi yang sekedar menggugurkan riwayatnya,
atau yang menunjukkan sangat lemahya riwayat yang disampaikannya, seperti:
؛ ال يكتب حديثه.ال يساوي شيء ؛ ليس بشيء؛ ضعيف جدا؛ رد حديثه؛ مردود احلديثTingkat keempat: penyifatan perawi yang menunjukkan ketertuduhan perawi
sebagai pendusta, pemalsu atau sejenisnya, tanpa menunjukkan penekanan, seperti:
لكذب؛ لوضع؛ متهم ال حيل أخذوا عنه؛فيه نظر؛ال يكتبوا حديثهيسرق احلديث؛ متهم Lafal-lafal yang menunjukkan ditinggalkan hadisnya,
لثقة؛هالك؛ذاهب احلديث؛ مرتوك احلديث .ال يعترب به؛ سكتوا عنه؛ ليس Tingkat kelima: penyifatan perawi yang mencederakan/menggugurkan
keadilannya secara tegas dalam bentuk mubalagah (berlebih-lebihan), jarh dengan
kedustaan atau pemalsuan, seperti:
.الدج ؛ وضاع؛ ابكذ Tingkatan keenam: penyifatan perawi dengan kecacatan yang menunjukkan
af’al at-tafdil dalam hal jarḥ, seperti:
55Ibid.; Rahman, Ikhtisar…, h. 316-318.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 53
مثله؛ ليس مثله يف الكذب؛ هو ركن الكذب؛ إليه منتهى يف الوضع؛ أكذب الناس .مل أرا كذTerhadap rijal yang tergolong dalam empat tingkatan terakhir ini, ulama sepakat untuk
tidak diperbolehkannya mengambil riwayat mereka dan tidak pula diamalkan. Berikut at-
Thahanawi menjelaskan, orang-orang yang di-jarḥ dengan salah satu lafal al-jarḥ –baik pada
tingkat keempat maupun kelima– di nilai gugur, hadisnya tidak ditulis, tidak dijadikan I’tibar,
dan tidak pula istisyhad. Sedang perawi yang di-jarh dengan lafal pada tingkat keenam tidak
boleh diriwayatkan sama sekali kecuali untuk menjelaskan keadaannya dan menolaknya.56
D. Syarat-Syarat al-Jarḥ wa at-Ta’dil
Al-jarḥ dan at-ta’dil mempunyai dua macam syarat, yaitu: pertama, syarat Ulama yang
boleh melakukan al-jarḥ dan at-ta’dil dan kedua, syarat diterimanya al-jarḥ dan at-ta’dil.
Adapun syarat ulama yang akan melakukan al-jarḥ dan at-ta’dil itu, sebagai berikut:
a. Berilmu, bertaqwa, warak dan jujur. Memberikan hukum terhadap orang lain dengan
jalan jarḥ dan ta’dil senantiasa membutuhkan keadilannya, seperti yang terdapat
dalam sifat-sifat ini.
b. Mengetahui sebab-sebab al-jarḥ dan at-ta’dil. Ibnu Hajar mengatakan bahwa tazkiyah
c. Mengetahui penggunaan lafal dan ungkapan bahasa Arab sehingga lafal yang
digunakan tidak terpakai kepada selain makna yang tepat dan tidak men-jarḥ dengan
lafal yang sebenarnya tidak digunakan untuk al-jarḥ.
d. Penilaian al-jarḥ dan at-ta’dil dari setiap orang yang ‘adil, baik laki-laki maupun
perempuan, merdeka maupun budak diterima.
e. Penilaian al-jarḥ dan at-ta’dil dari satu orang dapat dipadakan selama ia memenuhi
syarat sebagai penilai. Inilah pendapat kebanyakan ulama.57
Sementara syarat-syarat diterimanya al-jarḥ dan at-ta’dil itu, sebagai berikut:
a. al-jarḥ tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya.
b. Penilaian al-jarḥ secara umum, tanpa menjelaskan sebab-sebabnya terhadap periwayat
yang sama sekali tidak ada yang menta’dilnya dapat diterima.
c. al-jarḥ harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi penerimaannya.58
56Zafar Aḥmad aṭ-Ṭahanawi, Qawā`id fī `Ulūm al-Ḥadīṡ (Maktabah al-Matbu`ah al-Islamiyah, 1404 H/1984 M), h. 253.
57Nur ad-Din `Itr, Manhaj an-Naqd fi `Ulūm al-Ḥadīṡ (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 93-94.58Ibid., h. 96-100.; Rahman, Ikhtisar…, h. 310-311.
54 | Triansyah Fisa, M.T.H.
E. Prosedur Penetapan al-Jarḥ wa at-Ta’dil
Sebagian besar hukum-hukum syariat hanya dapat diketahui melalui pengutipan dan
periwayatan, maka ulama menempuh cara meneliti keadaan para periwayatnya dan
mencermati mereka yang berstatus ṡiqah lagi hāfiẓ. Ada beberapa teori yang dikemukakan
oleh para ulama ahli al-jarḥ dan at-ta’dil yang digunakan sebagai prosedur penetapan al-jarḥ
dan at-ta’dil, yaitu:
a. Jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian. Mereka akan menyebutkan sifat positif
maupun negatif seorang perawi. Sebagai contoh, perkataan Muḥammad bin Sirrin:
“Sungguh engkau telah berbuat zalim kepada saudaramu, bila engkau hanya
menyebutkan keburukannya saja, tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya”.
b. Kecermatan dalam meneliti dan menilai. Dengan mencermati pernyataan-pernyataan
ulama tentang al-jarḥ dan at-ta’dil dapat ditemukan kecermatan mereka dalam
meneliti dan kedalaman pengetahuan mereka tentang seluk-beluk perawi yang mereka
kritik.
c. Mematuhi etika al-jarḥ dan at-ta’dil dalam menyatakan penilaian tidak akan keluar
dari etika penelitian ilmiah. Ungkapan paling keras yang mereka kemukakan adalah
fulan waḍha (fulan tukang palsu), fulan każib (fulan tukang dusta), fulan yaftari al-
kāżiba ‘alā aṣ-ṣahabah (fulan membuat kedustaan atas diri sahabat) atau ungkapan-
ungkapan lain yang mereka berikan untuk orang yang memalsukan hadis.
d. Secara global menta’dil dan secara rinci dalam mentajriḥ. Dari ungkapan-ungkapan
para Imam yang men-jarḥ dan men-ta’dil dapat dilihat bahwa mereka tidak
menyebutkan sebab-sebab at-ta’dil mereka terhadap para perawi. Karena penyebab
pen-ta’dil-an seorang perawi itu sangat banyak, sehingga sulit bagi seseorang untuk
menyebut seluruhnya. Berbeda dengan al-jarḥ yang pada umumnya mereka jelaskan
sebabnya, seperti seringnya lupa, menerima riwayat secara lisan saja, keseringan
salah, kacau hafalannya atau tidak kuat hafalannya, melakukan dusta, tergolong
sebagai orang fasik dan lain-lain. Karena dianggap cukup menyebut satu sebab untuk
mengkritik sifat ‘adilnya atau daya hafalannya. Jumhur ulama menerapkan prinsip
semacam ini. Karena jarh hanya diperbolehkan demi kepentingan membedakan antara
yang ṡiqah dan yang ḍa’if (lemah).59
59Al-Khaṭīb, Uṡūl…, h. 265-267.; T.M. Hasby Ash-Shidieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 217-218.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 55
F. Cara Mengetahui Keadilan Seorang Perawi
Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan berikut:
a. Dengan kepopulerannya di kalangan para ahli ilmu, bahwa dia terkenal sebagai
seorang yang ‘adil. Seperti dikenalnya sebagai orang yang ‘adil di kalangan ahli ilmu,
misalnya Anas bin Malik, Sufyān aṡ-Ṡauri, Sya’ban bin al-Ḥajjāj, asy-Syāfi’ī, Ahmad
dan lain-lain. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang ‘adil di kalangan
para ahli ilmu, maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang
keadilannya.
b. Dengan pujian dari seseorang yang ‘adil (tazkiyah). Yaitu, ditetapkannya sebagai
perawi yang ‘adil oleh orang yang ‘adil pula, yang semula perawi yang dita’dilkan itu
belum dikenal sebagai rawi yang ‘ adil.60 Penetapan keadilan seorang rawi dengan
jalan tazkiyah ini hanya dapat dilakukan oleh, sebagai berikut:
- Seorang rawi yang ‘adil. Jadi, tidak perlu mengkaitkan dengan banyaknya orang
yang menta’dilkannya. Sebab jumlah itu bukanlah syarat untuk diterimanya riwayat
tersebut. Oleh karena, jumlah tersebut tidak menjadi syarat mutlak untuk
menta’dilkan seorang rawi. Demikian pendapat kebanyakan muḥaddiṡin, lain
halnya dengan pendapat para fuqaha yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua
orang dalam mentazkiyahkan seorang perawi.
- Setiap orang dapat diterima periwayatannya, baik laki-laki maupun perempuan,
orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat
mengadilkannya.
Selain dari ketetapan keadilan seorang rawi di atas, ketetapan tentang kecacatannya
juga dapat ditempuh dengan tiga jalan, sebagai berikut:
a. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam keaibannya. Misalnya,
seorang perawi telah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan
masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan.
b. Kemasyhuran seorang perawi akan keburukannya dapat dijadikan sebagai jalan
untuk menetapkan kecacatannya.
c. Berdasarkan pen-tajriḥ-an dari seorang yang dianggap ‘adil yang telah mengetahui
sebab-sebabnya dia cacat.61
60Abdul Mahdi, Ilmu Jarḥ wa at-Ta’dil Qawā`iduhu wa Aimmatuhu, (Mesir: Jami`ah al-Azhar, 1998),h, 29.
61Ibid., h. 79.
56 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Demikian ketetapan yang dipegangi oleh para muḥaddiṡin, sedang menurut para
fuqaha sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh dua orang laki-laki yang ‘adil.
G. Pertentangan Antara al-Jarḥ wa at-Ta’dil
Di antara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang
perawi. Ada sebagian ulama yang menta’dilkannya sedang yang lain mentajriḥnya. Dilihat
dari permasalahan ini sepertinya dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pertentangan
ulama itu diketahui sebabnya dan kedua, pertentangan itu tidak diketahui sebabnya. Adapun
terhadap pengkategorian yang pertama, sebab-sebab terjadinya adalah sebagai berikut:
1. Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi tersebut, ketika perawi masih
digolongkan sebagai orang yang fasik, sehingga para muḥaddiṡin men-tarjih perawi
tersebut. Kemudian, sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah si perawi
tersebut bertaubat, sehingga mereka menta’dilkannya. Menurut ‘Ajaj al-Khaṭīb, hal
tersebut bukanlah suatu pertentangan, artinya jelas yang dimenangkan adalah ulama
yang menta’dil.
2. Terkadang pula ada ulama yang mengetahui seorang perawi sebagai orang yang
memiliki daya hafalnya lemah, sehingga mereka men-tajrih perawi itu. Sementara,
ulama yang lain mengetahuinya sebagai oarang yang ḍabit, sehingga mereka
menta’dilkannya.
Namun, dalam hal sebab-sebab yang menjadi pertentangan ulama mengenai jarḥ dan
ta’dil-nya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka penentuan mana yang akan
diunggulkan dari pendapat ulama yang mentajrih atau yang men-ta’dil-nya. Dalam hal ini
‘Ajaj al-Khaṭib menuliskan tiga pendapat, sedang Fatchur Rahman membagikannya dalam
empat pendapat, sebagai berikut:
a. Al-jarḥ harus didahulukan dari pada at-ta’dil, meski yang men-ta’dil lebih banyak
dari pada yang men-tajrih. Menurut asy-Syaukani pendapat ini adalah pendapat
jumhur, alasanya orang yang men-tajrih mempunyai kelebihan mengetahui (cermat)
dan dapat melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli
oleh orang yang men-ta’dil-nya.
b. At-ta’dil harus lebih dulu didahulukan daripada al-jarḥ, bila yang menta’dil lebih
banyak. Karena banyaknya yang menta’dil dapat mengukuhkan keadaan perawi-
perawi yang bersangkutan. Pendapat ini tidak dapat langsung diterima, sebab yang
men-ta’dil harus lebih banyak jumlahnya, tidak memberitakan apa yang bisa
menyanggah pernyataan yang men-tajrih.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 57
c. Bila al-jarḥ dan at-ta’dil bertentangan, maka salah satunya tidak dapat didahulukan
kecuali salah satunya ada yang dapat menguatkan pernyataannya. Jika tidak terpaksa
di-tawaquf dari mengamalkannya sampai diketemukan hal yang dapat menguatkan
salah satunya.62
d. Mendahulukan at-ta’dil terhadap al-jarh, karena sebab keterangan jarh dalam meng-
aibkan si perawi kurang tepat, meng-aibkannya bukan sebab yang dapat mencacatkan
rawi dengan sebenarnya, apalagi bila dipengaruhi rasa benci.63
H. Kitab-Kitab Jarh wa at-Ta’dil
Kitab-kitab dalam bidang ini dimulai pada abad ke 2 H. kitab yang mula-mula sampai
kepada kita adalah kitab Ma’rifatu ar-Rijal karya Yahya bin Ma’in. baiklah, berikut kitab-
kitab jarh wa at-ta’dil tersebut:
a. Ma’rifatur-Rijāl, karya Yaḥya bin Ma’īn (158 H–233 H) yang masih dalam bentuk
manuskrip hingga abad ke-4 H yang berada di Dār al-Kutūb aḍ-Ḍahiriyah.64
b. Aḍ-Ḍu’afā´, karya Imam al-Bukhārī (194 H–252 H) dicetak di India tahun 1325 H
bersamaan dengan kitab aḍ-Ḍu’afā´ wa al-Matrukīn, karya Imam Aḥmad bin Syu’aib
‘Ali an-Nasa´i (215 H–303 H).
c. Al-Jarḥ wa at-Ta’dīl, karya ‘Abdur-Raḥman bin Abi Ḥātim ar-Rāzī (240 H–327 H).
merupakan kitab yang paling besar manfaatnya dalam keilmuan Jarḥ wa at-Ta’dīl,
memuat 18.050 biografi dalam 4 jilid besar. Kemudian dicetak kembali menjadi 9
jilid di India pada tahun 1375 H dengan penambahan mukadimah sebagai jilid
pertama, dan jilid aslinya masing-masing dibagi menjadi dua-dua jilid.
d. Aṡ-Ṡiqāt, karya Abi Ḥātim bin Ḥibbān al-Bustī (w. 354 H). kitab ini merupakan kitab
yang paling mudah mengadilkan seorang perawi. Karenanya hendaknya berhati-hati
dalam penta’dīlannya.
e. Al-Kāmil fi Ma’rifah Du’afa´ al-Muḥaddiṡīn wa ‘Ilal al-Ḥadīṡ, karya al-Ḥāfiḍ
‘Abdullah bin Muḥammad al-Jurjānī (277 H–365 H).
f.Mīzān al-I’tidāl, karya Imam Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad aż-Żahabī (673 H–
748 H). cetakan terakhir di Mesir tahun 1382 H/1963 M dalam 3 jilid, yang memuat
11.503 biografi.
62Al-Khaṭīb, Uṡūl…, h. 270.; Jalal ad-Din as-Suyuṭi, Tadrīb ar-Rawī (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1988M), h. 309.
63 Rahman, Ikhtisar…, h. 313.64Al-Khaṭīb, Uṡūl, h. 277.; Rahman, Ikhtisar…, h. 320.
58 | Triansyah Fisa, M.T.H.
g. Lisān al-Mīzān, karya al-Ḥāfid Ibnu Ḥajar al-’Asqalānī (773 H–852 H). kitab ini
memuat 14.343 biografi, dan dicetak di India tahun 1329-1331 H dalam enam jilid.65
65Ibid.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 59
Topik 12_ Ingkar Sunah (pengertian, sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama)
A. Pengertian dan Sejarah Awal
Dalam pengertian bahasa kata ingkar diartikan sebagai bentuk pembantahan terhadap
sesuatu dengan maksud tidak mengakuinya (mendustakannya).66 Sedang sunah sebagaimana
yang telah dijelaskan di awal pertemuan, segala bentuk perkataan, perbuatan, dan sifat atau
kebiasaan Nabi saw. yang hampir tidak pernah ditinggalkan.67 Secara definitif ingkar sunah
adalah sebuah gerakan intelektual yang meligitimasi diri untuk tidak mempercayaai otentisitas
dan orisinalitas sunah Rasul saw. secara keseluruhan atau sebagian saja.68 Hal ini didasari atas
dasar rasionalitas dan hawa nafsu yang meragukan eksistensi sunah sebagai dasar syariat,
karena mereka menganggap syariat sudah cukup terpenuhi dengan adanya Alquran.
Kepedulian terhadap Alquran di periode awal Islam mengakibatkan sebagian orang
kurang memperhatikan sunah Rasul, terlebih lagi saat Rasul melarang penulisan selain
Alquran. Sebenarnya keingkaran mereka disebabkan karena ketidakpahaman mereka akan
fungsi sunah terhadap Alquran,69 sebagaimana yang diceritakan oleh Imam al-Ḥākim dalam
kitab al-mustadrak ‘alā aṣ-ṣaḥīḥain70. Ini merupakan representatif gejala awal dari
munculnya ketidakpedulian terhadap sunah Rasul, padahal pada masa itu otentisitas hadis
Nabi tidak diragukan lagi.
Sebenarnya gejala ingkar sunah itu muncul dapat saja terjadi karena kesalahpahaman
atau kedangkalan seseorang terhadap sunah. Namun demikian, semakin tidak menghiraukan
Sunah tersebut, maka akan semakin jauh keingkaran itu terjadi dan bentuk pengingkaran pun
akan semakin mencuat. Sehingga mereka akan mencari pemecahan masalah yang mereka
hadapi hanya dalam Alquran semata. Itu pun jika mereka mampu memahaminya dengan baik,
yang sangat disayangkan adalah terhadap Alquran pun mereka juga terjadi kesalahpahaman.
Di Indonesia, menurut Mustafa Ali Yaqub, gejala ingkar sunah dimulai dari sikap
individual hingga akhirnya terbentuk sebuah kelompok, dalam catatan MUI ada satu
kelompok dengan nama Jama’ah Ahlul Qur’an, yang disebut sebagai gerakan ingkar sunah,
66Pengetian ini dimaksud dalam konotasi negatif, menolak integritas suatu kenyataan/fakta. TimPenyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 588. Dalam bahasa Arab ingkar ditulis أنكر(ankara) asal kata نكر (nakara). lihat al-Munawwir…, h. 1461.
67Lihat topik 1 tentang pengertian hadis, h.68Wahid, Studi Ilmu…, h. 171.69Zuhri, Hadis Nabi…, h. 15.70Ketika `Imrān bin Ḥuṣain mengajarkan hadis Nabi saw., bangkitlah seorang laki-laki dan mengatakan:
“Hai Abu Nujaid, berilah kami pelajaran Alquran saja”. Kemudian `Imrān berkata: Taukah kamu, seandainyakamu dan sahabat-sahabatmu menggunakan Alquran saja, apakah kamu dapat menemukan dalam Alquranbagaimana pelaksanaan salat dan hukum-hukumnya? Taukah kamu bagaimana cara mengeluarkan zakat dariemas, unta, sapi, dan harta lainnya? Mendengar jawaban itu orang tadi berkata: “Engkau telah menyadarkanku,semoga Allah tetap menyadarkanku”. Abu `Abdullāh al-Ḥākim an-Naisābūrī, al-Mustadrak `alā aṣ-Ṣaḥīḥain(Beirut: Dār al-Ḥirmīz, 1997), 5 Juz, Juz. I, h. 171.; Lihat juga, Wahid, Studi Ilmu…, h. 171.
60 | Triansyah Fisa, M.T.H.
didaerah Jakarta, Kuningan.71 Umumnya gejala ini terdapat di Irak.72 Hal ini dibuktikan
bahwa ‘Imrān bin Ḥuṣain dan Ayyub as-Sakhtiyānī, yang melontarkan kritikaan tersebtu
tinggal di Bashrah, Irak. Jawaban yang mereka berikan dalam membela sunah tersebut
berhubungan dengan pandangan segolongan murid-murid Irak yang dinilai telah mampu
mengabaikan sunah Nabi saw.73
Kemudian bukti ini didukung pula dengan kritikan yang dilontarkan Imam asy-Syafi’ī
terhadap ingkar sunah yang dilakukan oleh orang-orang Bashrah. Sehingga, dengan
kritikannya itu oleh ulama-ulama Arab ia diberi gelar sebagai nāṣirus-sunnah (penyelamat
sunah).
Di akhir abad kedua hijriah muncul pula kelompok-kelompok yang menolak sunah
sebagai salah satu rujukan syariat. Disamping itu juga ada golongan yang hanya menerima
hadis mutawatir saja, maksudnya hadis dalam kategori aḥad bukan merupakan hadis Nabi,
jadi tidak wajib diterima dan diikuti.74
Menurut Muṣṭafa as-Sibāī75 sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Azami, bahwa di
antara kelompok teologis yang menolak sunah adalah Khawarij. Namun, Azami
menyimpulkan kembali bahwa data itu tidak valid, sebab kaum Khawarij sudah punah dan
data primer mengenai mereka termasuk kitab-kitab yang mereka tulis sudah tidak ditemukan
lagi. Kecuali kelompok Ibadhiyah yakni bagian kecil dari kelompok Khawarij, dari
penelusuran Azami terhadap kitab-kitab mereka terdapat penjelasan bahwa mereka menerima
hadis Nabi yang dibawa oleh beberapa sahabat76 termasuk isteri Nabi saw. Dengan demikian,
tidak tepat jika harus mengatakan bahwa kaum Khawarij menolak sunah, sebab di antara
mereka ada yang menerima hadis Nabi sebagai syariat agama.77
Dalam literatur lain disebutkan juga bahwa kaum Muktazilah termasuk golongan yang
mengingkari sunah. Tidak mengherankan bila ada kelompok yang tidak senang dengan
kelompok ini kemudian menuduh mereka mengingkari sunah Rasul, sebab ada sikap seorang
muktazilah yang terkesan menolak sunah Rasul, seperti sikap an-Nazam menurut pandangan
71Gerakan ini telah dilarang secara resmi oleh para ulama dan Pemerintah sebagaimana tertera dalamfatwa hasil keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Tahun 1983 dan Keputusan Jaksa AgungRepublik Indonesia, Nomor 169/J.A/9/1983. Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran (Jakarta:Gema Insani, 2008), h. 39.
72Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 39.73Wahid, Studi Ilmu…, h. 172.74Ibid, h. 173.75Muṣṭafā Ḥusnī as-Sibā`ī, as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyrī` al-Islāmī (Beirut: Maktabah al-Islāmī,
1982), h. 127.76Sahabat yang dimaksud adalah Usman bin `Affan ra., Ali bin Abi Thalib ra., Abu Hurairah ra., Anas
bin Malik ra., dan Aisyah r.aha.77Zuhri, Hadis Nabi…, h. 15.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 61
al-Bagdadi dalam bukunya al-farq baina al-firaq. An-Nazam dinilai mengingkari mukjizat
Nabi dan segala kehujahan hadis Nabi. Dari keterangan as-Sibāī juga menyebutkan bahwa an-
Nazam juga mencela para sahabat Nabi, sehingga ini menjadi representasi bagi kaum muslim
menilai bahwa muktazilah termasuk golongan ingkar sunah.
Tetapi agaknya terlalu berlebihan jika harus mengatakan kaum Muktazilah sebagi
golongan ingkar sunah, karena ternyata di antara mereka seperti Abu al-Huzail al-’Allaf (w.
226 H), Muhammad bin ‘Abdul-Wahab al-Jubbai (w. 303 H), dan az-Zamakhsyari, memang
ditemukan ada sejumlah hadis yang mereka kritik dan ditinggalkan, yang mereka tolahk
adalah informasi yang dalam pandangan mereka anggap bukan sunah Rasul, padahal orang
Islam umumnya menilai itu adalah sunah Rasul. Dengan kata lain, walau bagaimana pun
hadis tetap dijadikan rujukan dalam memahami ajaran Islam. Perbedaan pendapat mereka
hanya sebatas hadis dalam kategori Ahad, tetapi tidak ada perbedaan terhadap hadis dalam
katagori mutawatir. Dari sini kesimpulan kita menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya
menolak sunah.78
Penolakan golongan Khawarij dan Muktazilah terhadap hadis ahad disebabkan adanya
keraguan terhadap validitas dari rawi-rawinya, sehingga mengamalkannya tidak memberikan
faedah. Kalau diperhatikan dengan baik alasan mereka itu sangan tidak otentik, jika mereka
mau meneliti Hadis dengan berpedoman kepada aturan-aturan dalam penerimaan hadis yang
dapat dijadikan sebagai hujah, tentu pandangan mereka akan berubah terhadap hadis-hadis
Nabi dan bahkan yang diperselisihkan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi generasi-
genarasi yang akan datang.
B. Keingkaran terhadap Kehujahan Sunah
1. Pada Masa Muttaqadimin
Sebagaimana yang disebutkan Imam asy-Syāfi’ī, ini terjadi di Baṣrah, yang
merupakan markas kaum Muktazilah. Mereka adalah orang-orang yang menentang para ahli
hadis. Dalam pernyataannya mereka meragukan kebenaran sanad. Hal ini disebabkan adanya
perawi yang salah atau ragu bahkan ada yang berdusta dan pembuat hadis palsu. Anggapan
mereka berlanjut terhadap pernyataan Alquran yang telah mencakup penjelasan segala
sesuatunya dengan cukup. Dalam hal ini terjadilah sunah bersifat ẓanni ṡubutnya (samar
ketetapan hukumnya), bertentangan dengan Alquran yang bersifat qaṭ'i ṡubutnya (sudah pasti
ketetapannya).
78Wahid, Studi Ilmu…, h. 174.; Zuhri, Hadis Nabi…, h. 16.
62 | Triansyah Fisa, M.T.H.
2. Pada Masa Mutaakhkhirin
Di antara tokoh yang menghidupkan kembali persoalan itu adalah Dr. Taufiq Shidqi.
Dia menulis pada majalah Al-Manar edisi 7 dan 12 dengan judul “al-Islam huwa al-Qur'an
wahdahu”79. Di dalamnya dipaparkan dasar untuk mengingkari sunah, berangkat dari firman
Allah swt.
نا يف الكتاب من شيء مث إىل رم حيشرون.ما فـرط ...Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlahmereka dikumpulkan. (al-An‘am: 38)
لكل شيء وهدى ور ... يا محة وبشرى للمسلمني.ونـزلنا عليك الكتاب تبـKami turunkan kepadamu al-kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu danpetunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (an-Naḥl: 89)Menurutnya kedua ayat tersebut telah mencakup segala sesuatu tentang agama, telah
disampaikan hukum bahkan perinciannya. Dia menambahkan, adalah mustahil kalau ada yang
tercecer dalam Alquran sedang Allah menjamin itu tidak akan terjadi.80 Dengan demikian,
seandainya hadis merupakan hujjah dalam Islam, pasti difirmankan tentang penjagaan hadis.
Pernyataan lain ia sebutkan jika sunah merupakan hujah, tentu Nabi akan
memerintahkan sahabat untuk menulisnya,81 dan mereka akan mengumpulkan dan
membukukannya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah berikut;
79Lihat Muhammad Taufiq Shidqi, al-Islam Huwa al-Qur'an wahdahu (majalah al-Manar, 1906), 515-24.80
له حلافظون. حنن نـزلنا الذكر وإ إSesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan Kami pulalah yang memeliharanya. (al-Ḥijr: 9)
8181Ia menyebutkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khudri ra. mengenai larangan Nabidalam menulis hadis di awal periwayatan Hadis yang berbarengan dengan Alquran.
من كذب عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال تكتبوا عين، ومن كتب عين غري القرآن فليمحه، وحدثوا عين، وال حرج، و .ليتبوأ مقعده من النارمتعمدا ف-قال مهام: أحسبه قال -علي
Dari Abu Sa‘id al-Khudri ra., Nabi saw. bersabda: Janganlah kalian menulis dariku, barangsiapamenulis dariku selain al-Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa.Barangsiapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja,maka henkdaklah menyiapkan tempatnya dari neraka. Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim an-Naisāburī,Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 3004 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), h. 1468
Sebenarnya larangan itu bersifat sementara atau hanya dkhususkan pada orang-orang tertentu yangdalam kekhawatiran Rasul mereka akan menyalin keduanya dalam lembaran yang sama sehingga akan sulitmembedakan antara Alquran dengan sabda Rasul. Dengan hadirnya pernyataan Rasul pada saat penaklukan kotaMakah mengenai perintah penulisan Hadis yang diizinkan Rasul oleh beberapa orang sahabat untuk Abu Syah,perintah ini membuktikan bahwa hadis larangan itu bersifat sementara atau bersifat khusus. an-Naisāburī, ṢaḥīḥMuslim, hadis no. 1355, h. 635.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 63
تـقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال.وال Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintapertanggungan jawabnya. (al-Isrā': 36)
إن تـتبعون إال الظن وإن أنـتم إال خترصون....Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalahberdusta. (al-An‘am: 148)
Berikut ia juga menyebutkan mengenai sabda nabi sendiri bahwa sunah bukanlah
hujah dalam Islam, sabda nabi:
Sesungguhnya hadis akan tersebar dariku, maka apabila hadis itu mendatangkansesuatu yang sesuai dengan Alquran berarti dia benar dariku, tetapi apabila itumembawa sesuatu yang bertentangan dengan Alquran, maka itu bukan dari aku.
Sesuatu yang baru yang belum pernah disampaikan Alquran, berarti bertentangan
dengan Alquran dan tidak bisa menjadi hujah. Jika apa yang disampaikan dalam hadis sudah
ada dalam Alquran, untuk apa mengambil hadis dan tidak mengambil langsung dari Alquran.
C. Jawaban Terhadap Keingkaran Sunah
Terhadap dalil yang disampaikan oleh para pengingkar Muṣṭafa as-Sibā‘ī memberikan
jawaban sebagai berikut:82
1. Yang terkandung dalam Alquran itu bersifat mendasar, berupa konsep dan kaidah-kaidah
umum, hanya sebagian yang diungkapkan secara jelas dan terperinci. Dan bagian
penjelasan itulah yang diserahkan kepada Rasulullah melalui hadisnya.
2. Jaminan Allah untuk menjaga aż-Żikr bukanlah berarti hanya Alquran tetapi mencakup
Sunah dan segenap syariat dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Hal ini dapat
dibuktikan dalam an-Naḥl: 43 yang berbunyi :
رسلنا من ق هيما وما ا اال نو لال ر هلوا فاس .ان كنمت ال تعلمونراKami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beriwahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyaipengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
3. Semuanya bukanlah bermaksud untuk memalsukan hadis, tetapi menurut Muhammad
Abu Zahwin adalah karena uzur yang memaksa atau ijtihad mereka disebabkan ada
perubahan dalam masyarakat.
4. Tidak benar ketika disebutkan para ulama pada abad kedua menilai kesahihan hadis
hanya dari segi matannya. Mereka menyaring hadis dan membuat ketentuan dalam
prosesnya dari segi matan dan sanadnya.
82Zuhri, Hadis Nabi…, h. 20-22.
64 | Triansyah Fisa, M.T.H.
5. Tindakan mereka itu adalah tindakan kaum orientalis yang tidaklah benar. Mereka
melontarkan tuduhan itu karena terbawa oleh kebencian mereka terhadap Islam dan
berusaha kuat untuk merobohkan Islam.
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 65
Topik 13_Metode Takhrij Hadis
Takhrij Hadis merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian hadis. Pada masa
awal, penelitian hadis telah dilakukan oleh para ulama salaf yang kemudian hasilnya telah
dikodifikasikan dalam berbagai buku hadis. Mengetahui masalah takhrij, kaidah, dan
metodenya adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu syar’i,
agar mampu melacak suatu hadis sampai pada sumbernya.
Pada mulanya ilmu Takhrij Hadis bukan suatu kebutuhan yang diharuskan oleh para
ulama dan peneliti hadis, karena pengetahuan mereka tentang sumber hadis ketika itu sangat
luas dan baik. Bahkan, hubungan mereka dengan sumber hadis pun sangat kuat sekali, apabila
mereka ingin membuktikan ke-shahih-an sebuah hadis, mereka mampu menjelaskan sumber-
sumber hadis dari berbagai kitab-kitab hadis, metode dan cara-cara penulisan kitab-kitab
hadis itu mereka ketahui.
Namun ketika para Ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber dari suatu
hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan setelah berkembangnya karya-
karya Ulama dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Sejarah, yang memuat hadis-hadis Nabi saw. dan
kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka ulama-ulama Hadis terdorong untuk
melakukan Takhrij terhadap karya-karya tersebut.
Kebutuhan takhrij meenjadi sangat perlu, karena orang yang mempelajari ilmu tidak
akan dapat membuktikan (menguatkan) dengan suatu hadis atau tidak dapat
meriwayatkannya, kecuali setelah para ulama yang telah meriwayatkan hadis dalam kitabnya
dengan dilengkapi sanadnya. Karena itu, masalah takhrij menjadi kebutuhan setiap orang
yang membahas atau menekuni ilmu-ilmu syar’i dan yang sehubungan dengannya.
A. Pengertian dan Tujuan
1. Pengertian Takhrij Hadis
Takhrij diartikan dengan pengertian yang bermacam-macam, dan yang populer
diantaranya adalah al-istinbath (mengeluarkan), al-tadrib (melatih atau membiasakan), al-
tawjih (menghadapkan).83
Secara bahasa, takhrij perubahan kata dari kharaja, kharaja - yakhruju - khuruujan
atau dari kata akhraja yang mengandung arti mengeluarkan,84 menerangkan maksud,
menyelesaikan, dan berlatih.85 Bentuk lain dari kharaja, yaitu : Akhtaraja dengan makna yang
83M. Isa Bustamin, Metodologi Kritik Hadis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 2884Ahmad Warson Munawwrir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977), h. 33085Bustamin, Metodologi Kritik Hadis, h. 28
66 | Triansyah Fisa, M.T.H.
sama, yaitu mengeluarkan.86 Ahmad dan Mudzakir juga mengatakan maksud yang sama
dengan bentuk lain dari kata kharaja-yukhariju-takhrijan yang artinya mengeluarkan,
menampakkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan.87 Maksudnya, menampakkan
sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang masih tersembunyi. Penampakan yang dimaksudkan
bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi mencakup nonfisik yang memerlukan tenaga dan
pikiran seperti makna kata istikhraj yang berarti mengeluarkan hukum dari nash al-quran dan
al-ḥadits.88
Istilah Istikhraj dalam ilmu hadis yaitu, bahwa seorang hafiz (ahli hadis)menentukan satu kitab kumpulan hadis karya orang lain yang telah disusun sanadnya,kemudian dia mentakhrij hadis-hadisnya dengan sanadnya sendiri dengan jalur lainpenyusun kitab tersebut. Akan tetapi, jalur sanadnya bertemu dengan sanad penulisbuku tersebut pada gurunya atau guru dari gurunya dan seterusnya hingga Sahabatpenerima hadis dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak datang dari sahabat yanglain, melainkan harus dari hadis sahabat itu sendiri.89
Sebagai contoh, seorang mukharij atau pentakhrij bermaksud melakukan istikhraj
terhadap Kitab hadis Bukhari. Hadis yang dicontohkan adalah hadis tentang niat, yaitu :
Hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanad “al-Humaidi dari Sufyan bin
Uyainah dari Yahya bin Sa’id al-Anshari dari Ibrahim al-Taimi dari al-Qamah bin Waqqash
al-Laitsi dari ‘Umar bin al-Khaththab. Seorang mustakhrij akan menyandarkan hadis
tersebut dengan sanadnya sendiri kepada gurunya Bukhari (al-Humaidi), atau kepada Sufyan
bin Uyainah (sebagai guru dari gurunya Bukhari), jika tidak kepada Ibn Uyainah maka dia
akan menyandarkan kepada Yahya bin Sa’id al-Anshari melalui jalur Malik atau ats-Tsauri
atau Ibn al-Mubarak atau ‘Abd al-Rahman bin Mahdi atau para perawi selain mereka yang
meriyawatkan hadis tersebut dari Yahya bin Sa’id al-Anshari, yang jumlahnya menurut
Ulama Hadis mencapai 700 orang. Demikian seterusnya, jika tidak kepada Yahya maka dia
meriyawatkan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri yang disandarkan kepada at-Taimi, atau
kepada al-Qamah bin Waqqash, atau kepada Umar bin Khaththab, sahabat yang menjadi
sanad terakhir dari Bukhari. Dalam hal ini, dia tidak boleh menyandarkannya kepada sahabat
yang lain meskipun sahabat tersebut meriwayatkan hadis niat tersebut, yang rangkaian
sanadnya dinilai dha’if oleh para Ulama Hadis. Jadi, apabila pada tingkat sahabat sanadnya
86Munawwir, Al-Munawwir, h. 33087Muhammad Ahmad dan Mudzakir, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13188Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 11589Nawir Yuslem, Sembilan Kitab Induk Hadis (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 15090Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981 M), h. 2
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 67
tidak bertemu dengan sanadnya Bukhari, maka kegiatan ini tidak dinamakan dengan istikhraj,
melainkan hadis musnad yang dengan periwayatan sendiri.
Pengertian takhrij menurut istilah adalah,
“Menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telahdiriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika
diperlukan.”
Fatchur Rahman meng-istilahkan pengertian takhrij dengan Usaha mencari derajat
sanad dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang kitab. Misalnya,
Takhrij Ahadisi al-Kasysyaf, kitab yang menjelaskan derajat hadis yang terdapat dalam kitab
tafsir al-Kasysyaf.
2. Tujuan dan Manfaat Takhrij Hadis
Ilmu takhrij merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapat perhatian serius
karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis itu berasal.
Disamping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya
dalam menentukan kualitas sanad hadis.94
Penguasaan tentang ilmu Takhrij sangat penting, bahkan merupakan suatu keharusan
bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu-ilmu kasyariahan, khususnya yang
menekuni bidang hadis dan ilmu hadis. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dan metode
takhrij, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada suatu hadis di
dalam sumber-sumbernya yang asli yang pertama kali disusun oleh para Ulama
pengkodifikasi hadis. Dengan mengetahui hadis tersebut dari sumber aslinya, maka akan
dapat diketahui sanad-sanadnya. Hal ini akan memudahkan untuk melakukan penelitian sanad
dalam rangka untuk mengetahui status dan kualitasnya. 95
Dengan demikian Takhriju al-Hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang di
takhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut.
Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan
91Nawir, Sembilan, h. 15192Mahmud al-Tahhan, Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid, terj. Ridlwan Nasir, (Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 1995), h. 593Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, cet. 10 (Bandung: PT Alma’arif, 1974), h. 34-3594Al-Thahhan, Usul al-Takhrij, h. 9995Nawir, Sembilan, h. 154
68 | Triansyah Fisa, M.T.H.
kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku. Sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-
usul maupun kualitasnya. Menurut Syuhudi, minimal ada tiga hal yang menjadi tujuan
penting takhrijul hadis dalam melaksanakan penelitian hadis. Berikut ketiga hal tersebut;
Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, untuk mengetahui seluruh
riwayat bagi hadis yang akan diteliti, dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan
mutabi’.96
Adapun manfaat takhrij hadis sebagai berikut:
a. Menghimpun sejumlah sanad hadis, dengan takhrij seseorang dapat menemukan sebuah
hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja,
atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah sanad.
b. Mengetahui referensi beberapa buku hadis, dengan takhrij seseorang dapat mengetahui
siapa perawi suatu hadis dan yang diteliti dan didalam kitab hadis apa saja hadis tersebut
didapatkan.
c. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung (muttashil) dan yang terputus (munqothi’)
dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam
periwayatan.
d. Mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhoif, tetapi
melalui sanad lain hukumnya sahih.
e. Meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan lighairihi karena adanya dukungan
sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya, atau meningkatnya hadis hasan
menjadi shahih ligairihi dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih
tinggi kualitasnya.
f. Mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana
kritikan yang disampaikan.
g. Seseorang yang melakukan takhrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan hadis.97
h. Dengan takhrij dapat diketahui banyak sedikitnya beberapa jalur periwayatan suatu hadis
yang sedang menjadi topik kajian.
i. Dengan takhrij akan diketahui kuat dan tidaknya periwayatan. Makin banyaknya jalur
periwayatan akan menambah kekutan riwayat, sebaliknya tanpa dukungan periwayatan
lain maka berarti kekuatan periwayatan tidak bertambah.
j. Dengan takhrij kekaburan suatu periwayatan, dapat diperjelas dari periwayatan jalur
isnad yang lain. Baik dari segi rawi, isnad maupun matan hadis.
96M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h. 4497Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 118
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 69
k. Dengan takhrij akan dapat ditentukan status hadis shahih lidzatihi atau shahih lighairihi,
hasan lidzatihi atau hasan lighairihi. Demikian juga akan diketahui istilah hadis
mutawatir, masyhur, aziz, dan gharib.
l. Dengan takhrij akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan atau wawasan yang lebih
luas tentang berbagai periwayatan dan beberapa hadis terkait.
m. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui
bahwa hadis tersebut adalah maqbul (dapat diterima), sebaliknya orang yang tidak
mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud (ditolak).
n. Mengetahui keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah
saw. yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis
tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.98
Manfaat dari ilmu takhrij hadis sangat banyak sekali sehingga sudah sewajarnya setiap
cendekiawan muslim untuk memperhatikan ilmu ini dan mempelajarinya serta
mengembangkannya sehingga akan jelas derajat suatu hadis.
B. Proses
Melegakan rasanya apabila dalil syarak yang digunakan dalam melaksanakan syariat
agama adalah dalil yang diriwayatkan secara mutawatir. Namun, seringkali kita dapati sebuah
hadis yang tidak tau dari kitab mana hadis itu dimuat. Ada lima metode yang digunakan oleh
para ulama dalam menulusuri/men-takhrij suatu hadis, berikut paparan kelima metode
dimaksud;
a. Takhrij Melalui Permulaan Kata Matan Hadis
Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan
metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah.
Misalnya, apabila akan men-takhrij hadis yang berbunyi;
Untuk mengetahui lafaz lengkap dari penggalan matan tersebut, langkah pertama yang
dilakukan adalah menelusuri penggalan matan itu pada urutan awal matan yang memuat
penggalan matan yang dimaksud. Dalam kamus yang disusun oleh Muhammad fuad Abdul
Baqi, penggalan hadis tersebut terdapat di halaman 815 juz I. Dalam catatan kakinya hadis ini
terdapat dalam kitab Sahih Bukhari bab al-Ḥazari min al-Gaẓab Juz 19 halaman 72 no. 5649,
98Ahmad Husain, Kajian Hadis Metode Takhrij, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustar,1993), 107
70 | Triansyah Fisa, M.T.H.
dalam kitab Sahih Muslim bab Faḍli Man Yamliku Nafsahu ‘Inda al- Gaẓab Juz 13 halaman
19 no. 4723. Setelah diperiksa, bunyi lengkap matan hadis yang dicari adalah:
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “(Ukuran) orang yang kuat(perkasa) itu bukanlah dari kekuatan orang itu dalam berkelahi, tetapi yang disebutsebagai orang yang kuat adalh orang yang mampu menguasai dirinya tatkala diamarah”.Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar
bagi seorang mukharrij untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Akan tetapi,
metode ini juga mempunyai kelemahan yaitu, apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz
pertamanya sedikit saja, maka akan sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Sebagai
contoh;
Berdasarkan teks di atas, maka lafaz pertama dari hadis tersebut adalah iza atakum اذا )
Namun, apabila yang diingat oleh .(اتاكم mukharrij sebagai lafaz pertamanya adalah law
atakum atau (لو اتا كم ) iza ja’akum maka hal tersebut tentu akan menyebabkan ,(اذاجاءكم )
sulitnya menemukan hadis yang sedang dicari, karena adanya perbedaan lafaz pertamanya,
meskipun ketiga lafaz tersebut mengandung arti yang sama.99
b. Takhrij Melalui Kata dari Matan Hadis
Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam
matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja.100 Dalam metode ini tidak digunakan
huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya sehingga pencarian hadis-hadis
yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah
manakala menitikberatkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang
penggunaanya.
Kitab yang berdasarkan metode ini di antaranya adalah kitab Al-Mu`jam Al-Mufahras
li Al-faz Al-Hadis An-Nabawi. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di dalam
Sembilan kitab induk hadis sebagaimana yaitu; Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmizi,
99 Yuslem., Sembilan, h. 160-161100 Ibid., h. 161
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 71
Sunan Abu Daud, Sunan Nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Muwaththa’ malik, dan
Musnad Imam Ahmad.
Contohnya pencarian hadis berikut;
Dalam pencarian hadis di atas, pada dasrnya dapat ditelusuri melalui kata-kata naha
(نھى) ta’am yu’kal ,(طعام) (یؤكل ) al-mutabariyaini Akan tetapi dari sekian kata yang .(المتباریین )
dapat dipergunakan, lebih dianjurkan untuk menggunakan kata al-mutabariyaini (المتباریین )
karena kata tersebut jarang adanya. Menurut penelitian para ulama hadis, penggunaan kata
tabara .di dalam kitab induk hadis (yang berjumlah Sembilan) hanya dua kali (تبارى)
Penggunaan metode ini dalam men-takhrij suatu hadis dapat dilakukan dengan
mengikuti langkah-langkah berikut;101
Langkah pertama, adalah menentukan kata kuncinya yaitu kata yang akan
dipergunakan sebagai alatuntuk mencari hadis. Sebaiknya kata kunci yang dipilih adalah kata
yang jarang dipakai, karena semakin bertambah asing kata tersebut akan semakin mudah
proses pencarian hadis. Setelah itu, kata tersebut dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dan
berdasarkan bentuk dasar tersebutdicarilah kata-kata itu di dalam kitab Mu’jammenurut
urutannya secara abjad (huruf hijaiyah).
Langkah kedua, adalah mencari bentuk kata kunci tadi sebagaimana yang terdapat di
dalam hadis yang akan kita temukan melalui Mu’jam ini. Di bawah kata kunci tersebut akan
ditemukan hadis yang sedang dicari dalam bentuk potongan-potongan hadis (tidak lengkap).
Mengiringi hadis tersebut turut dicantumkan kitab-kitab yang menjadi sumber hadis itu yang
dituliskan dalm bentuk kode-kode sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Metode ini memiliki beberapa kelebihan yaitu; Metode ini mempercepat pencarian
hadis dan memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam
matan hadis. Selain itu, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan yaitu; Terkadang suatu
hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan
kata-kata lain.
c. Takhrij Berdasarkan Periwayat Sahabat
Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis,
lalu kita mnecari bantuan dari tiga macam karya hadis yakni;
101 Yuslem., Sembilan, h. 164
72 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Al-Masanid (musnad-musnad). Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama
sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini
hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.
Al- ma`ajim (mu`jam-mu`jam). Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad
para sahabat atau syuyukh (guru-guru) sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui
nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya.
Kitab-kitab Al-Atraf. Kebanyakan kitab al-atraf disusun berdasarkan musnad-musnad
para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti
mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang
ditunjukkan oleh kitab-kitab al-atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara
lengkap.102
Kelebihan metode ini adalah bahwa proses takhrij dapat diperpendek. Akan tetapi,
kelemahan dari metode ini adalah ia tidak dapat digunakan dengan baik, apabila perawih yang
hendak diteliti itu tidak diketahui.
d. Takhrij Berdasarkan Tema Hadis
Metode ini berdasrkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu untuk melakukan
takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan
ditakhrij dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun
menggunkan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus
yang demikian seorang mekharrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin
dikandung oleh hadis tersebut. Contoh :
Dibangun Islam atas lima pondasi yaitu : Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allahdan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayarkan zakat,berpuasa bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.
Hadis di atas mengandung beberapa tema yaitu iman, tauhid, shalat, zakat, puasa dan
haji. Berdasarkan tema-tema tersebut maka hadis di atas harus dicari didalam kitab-kitab
hadis dibawah tema-tema tersebut. Cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftah Kunuz As-
Sunnah yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan.
102 Al-Ṭahhan., Uṣul al-Takhrij, h. 26-30
Pengantar Studi Ilmu Hadis | 73
Dari keterangan di atas jelaslah bahwa takhrij dengan metode ini sangat tergantung
kepada pengenalan terhadap tema hadis. Untuk itu seorang mukharrij harus memiliki
beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fiqih secara khusus.103
Metode ini memiliki kelebihan yaitu: Hanya menuntut pengetahuan akan kandungan
hadis, tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Akan tetapi metode ini juga
memiliki berbagai kelemahan, terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh
seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya, maka metode ini tidak
mungkin diterapkan.
e. Takhrij Berdasarkan Status/Keadaan Hadis
Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis
dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya
tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti
hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan
membuka kitab-kitab seperti di atas dia telah melakukan takhrij al hadis.
Kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses takhrij. Hal ini karena
sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadis sangat
sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit. Namun, karena cakupannya sangat
terbatas, dengan sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya-karya sejenis, hal ini
sekaligus menjadi kelemahan dari metode ini.
Kitab kitab yang disusun berdasarkan metode ini:
Al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akbar al-Mutawatirah karangan Al-Suyuthi.
Al-Ittihafat al-Saniyyat fi al-Ahadis al-Qadsiyyah oleh al-Madani.
Al-Marasil oleh Abu Dawud, dan kitab-kitab sejenis lainnya.104
C. Contoh Proses Takhrij Hadis
Lihat lampiran
103 Yuslem, Sembilan, h. 166-167104 Yuslem, Sembilan, h. 168
74 | Triansyah Fisa, M.T.H.
Daftar Pustaka
Al-Afriqī, Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr, Lisan al-’Arabi, Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, t.t.Al-Aṡīr, Al-Jazirī Ibnu, Jāmi’ al-Uṣūl fi Aḥādīs ar-Rasūl, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr, t.t.Ḥanbal, Aḥmad bin, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, Beirut: Dār Iḥyā´ at-Turāṡ al-’Arabī, t.t.Husain, Abu Lubabah, al-Jarh wa at-Ta’dil, Riyad: Dār al-Liwa’, 1394 H/ 1974 M.‘Itr, Nur ad-Din, Manhaj an-Naqd fi ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Kaṡīr, Abu al-Fida´ Isma’īl bin, Tafsīr al-Qur´ān al-’Aḍīm, Qāhirah: Mu´assasah Qurṭubah,1421 H/2000 M.
Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajāj, Uṣūl al-Ḥadīs, Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.
Al-Mahdi, ‘Abd, Ilmu Jarḥ wa at-Ta’dil Qawā’iduhu wa Aimmatuhu, Mesir: Jami’ah al-Azhar, 1998.
Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: PustakaProgresif, 2002.
An-Naisāburī, Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim bin Kausyaż al-Qusyairi, Ṣaḥīḥ Muslim, 5Juz, Beirut: Dār Iḥya´ at-Turaṡ al-’Arabī, t.t.
Rahman, Fatchur, Ikhtisar Mushthalahul Hadis, Bandung: PT Alma’arif, 1974.Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
As-Suyuṭi, Jalal ad-Din, Tadrīb ar-Rawī, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1988 M.
At-Ṭahanawi, Zafar Aḥmad, Qawā’id fi ‘Ulūm al-Ḥadīṡ (Maktabah al-Matbu’ah al-Islamiyah,1404 H/ 1984 M.
At-Tirmiżī, Muḥammad bin ‘Īsa, Sunan at-Tirmiżī, Beirut: Dār Iḥyā´ at-Turāṡ al-’Arabī, t.t.Ahmad, Muhammad dan Mudzakir, Ulumul Hadis, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981 M.
Bustamin, M. Isa, Metodologi Kritik Hadis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Husain, Ahmad, Kajian Hadis Metode Takhrij, Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustar,1993.
Ismail, M. Syuhudi, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
Khan, Abdul Majid, Ulumul Hadis, Jakarta: Amzah, 2011.
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1977.
Rahman, Fatchur, Ikhtisar Musthalahul Hadis, cet. 10, Bandung: PT Alma’arif, 1974.
Al-Tahhan, Mahmud, Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid, terj. Ridlwan Nasir, Surabaya:
PT. Bina Ilmu, 1995.
Yuslem, Nawir, Sembilan Kitab Induk Hadis, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.