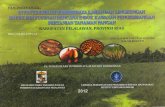PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA MALANG
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA MALANG
PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA
MALANG
Dian Lisna Wati
ABSTRAK:
Jumlah penduduk yang meningkat dan pertumbuhankegiatan ekonomi yang pesat berdampak pada kebutuhanlahan, seperti permukiman, industry, jasa sehinggaterjadi alih fungsi lahan pertanian karena lahanterbatas. Tidak terkecuali di Kota Malang. Di kota inisudah banyak daerah-daerah yang dulunya digunakansebagai lahan pertanian kini telah berubah menjadibangunan-bangunan seperti pertokoan, bank, sekolah,kantor dan lain sebagainya. Hal ini berakibat padaberkurangnya produksi pertanian di Kota Malang bahkandalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.Selain itu, tempat peresapan air di Kota Malang inimenjadi berkurang dan tergantikan oeleh bangunan-bangunan yang menutupi tanah sebagai tempat resapan air.Oleh sebab itu, perlu adanya pemberlakuan peraturanuntuk mencegah semakin sedikitnya lahan pertanian diKota Malang sehingga produksi pertanian dan daerahperesapan air di Kota Malang tidak akan berkurang.Kata kunci: penggunaan lahan, alih fungsi lahan.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan suatu kota akan berimplikasi terhadap
peningkatan kebutuhan lahan yang digunakan untuk
mewadahi kegiatan penduduk. Sejak manusia pertama kali
menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur
utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Di atas
lahan ini penduduk melakukan kegiatannya baik secara
individu maupun kelompok. Karena semua aktivitas
dilakukan di atas lahan, maka akan terjadi persaingan
penggunaan lahan. Kecenderungan dari persaingan ini
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di
daerah hinterland di mana lahan persawahan masih
tersedia cukup luas.
Selain itu, seiring pertumbuhan populasi dan
perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan
penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya
menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan
jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi,
serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi
sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-
angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.
Di Kota Malang sendiri tidak luput dari adanya
perubahan fungsi lahan-lahan pertanian. Sebenarnya
Kota Malang sebagian besar penduduk memiliki mata
pencaharian disektor pertanian. Sampai saat ini, sektor
pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan
penting dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan
kerja, dan penyediaan pangan. Namun akhir-akhir ini
banyak yang lahan pertanian mulai berubah fungsi. Alih
fungsi lahan banyak terjadi di daerah Klojen. Namun
daerah-daerah lain seperti Kedungkandang, Lowokwaru,
Sukun, dan Blimbing juga sudah menunjukan alih fungsi
lahan yang pesat. Berkembangnya perumahan, sektor
industri dan pariwisata yang tidak dapat dibendung
menjadi penyebab utama alih fungsi lahan di daerah ini.
Perubahan spesifik dari penggunaan untuk
pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang
kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi)
lahan (Iqbal dan Sumaryanto, 2007), kian waktu kian
meningkat. Khusus untuk di Kota Malang, fenomena ini
tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di
kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius
dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan
pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam
kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka
panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.
Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan
nonpertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal
itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi
ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah
perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan
berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata
ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan
pertanian wilayah dan nasional (Winoto, 2005).
Masalah alih fungsi lahan dapat diatasi bila
pemerintah daerah sangat ketat dalam hal penataan
ruang. Pemerintah harus tegas dalam melarang
pembangunan perumahan dan industri yang hendak
menggunakan lahan di kawasan pertanian. Alih fungsi
lahan dapat dicegah dengan menjadikan sektor pertanian
sebagai lapangan usaha yang menarik dan bergengsi
secara alami. Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa
kendali dapat menimbulkan persoalan ketahanan pangan,
lingkungan dan ketenagakerjaan (Syahyuti dkk, 2007).
Oleh karena itu, selain untuk melihat laju alih
fungsi lahan penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui daerah pertanian mana saja yang mengalami
alih fungsi dan dampaknya terhadap kecukupan pangan
serta apa saja yang menjadi motivasi atau faktor yang
mendorong masyarakat mengalihfungsikan lahan serta
strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mencegah
terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian.
Faktor yang Mempengaruhi Pengalihfungsian Lahan di Kota
Malang
Permasalahan lingkungan tidak pernah terlepas
dari tindakan para agen atau manusia yang melakukan
pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang terbuka
hijau yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap
keseimbangan lingkungan. Padahal sawah itu sangat
membantu produksi pangan yang sangat dibutuhkan oleh
para manusia.
Angka alih fungsi tanah pertanian ke non
pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam.
Sensus pertanian 2003 menyebutkan selama periode 2000-
2002 total luas tanah sawah di Indonesia yang
dikonversi ke penggunaan lain mencapai 563.000 hektar
atau rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun. Dengan luas
sawah 7,75 juta hektar pada tahun 2002, pengurangan
luas sawah akibat konversi lahan mencapai 7,27% selama
3 tahun atau rata-rata 2, 42% per tahun (Badan Pusat
Statistik (BPS), 2004).
Di Kota Malang, Jawa Timur yang luas wilayah
sebesar 110,06 km² dari tahun ke tahun terus menyusut
karena beralihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan
perumahan (permukiman) maupun sebagai kawasan yang
digunakan untuk perekonomian. Kepala Dinas Pertanian
Kota Malang Ninik Suryantini, Selasa, mengakui, tahun
2007 luas lahan pertanian di daerah itu mencapai 1.550
hektar, tahun 2009 menyusut menjadi 1.400 hektar dan
tahun ini tinggal 1.300 hektare (Sukarelawati, 2012).
Di Kecamatan Klojen yang merupakan pusat kota sudah
tidak ada lagi persawahan yang diakibatkan oleh
pembangunan sarana umum yang terus bertambah. Sedangkan
di daerah Lowokwaru memiliki lahan pertanian dengan
rincian jenis sawah yang dominan adalah sawah irigasi
tehnis seluas 1.523,343 ha dan sederhana non tehnis
seluas 6.918,156 ha. Sawah dapat difungsikan sebagai
lahan pertanian dengan hasil utama padi. Lokasi
persawahan terdapat di wilayah Merjosari,
Tunggulwulung, Tasikmadu. (Website Kecamatan Lowokwaru,
2014)
Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian
cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan
jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian.
Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat
kecenderungan tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika
di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam
waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih
fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal
tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan
dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di
suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di
lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk
pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya
mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor
lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di
sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan
selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya
untuk menjual lahan. Wibowo (1996) menambahkan bahwa
pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk
setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-
lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses
alih fungsi lahan.
Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian
yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah.
Hal tersebut disebabkan oleh :
1. Kepadatan penduduk di kota yang mempunyai
agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih
tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering,
sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih
inggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan
dengan daerah yang memungkinkan untuk membangun
sektor industri.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya.
Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih
baik dari pada wilayah lahan kering
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan
industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat
di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah
dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa)
ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.
Sedangkan menurut Lestari (2009) proses alih
fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian yang
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga
faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi
lahan sawah yaitu:
1. Faktor Eksternal.
Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya
dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun
ekonomi.
2. Faktor Internal.
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan
oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian
pengguna lahan.
3. Faktor Kebijakan.
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan
perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada
aspekregulasi atau peraturan itu sendiri terutama
terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi
pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang
dikonversi.
Menurut penelitian yang dilakukan, faktor yang
paling mempengaruhi pengalihan fungsi lahan pertanian
yang ada di Kota Malang adalah pertumbuhan pada sektor
perekonoman dan industri yang membutuhkan banyak lahan
untuk melakukan kegiatannya. Banyak sekali bangunan
yang dibangun untuk pabrik-pabrik dan pertokoan.
Disetiap daerah sudah banyak toko-toko mulai dari yang
sederhana sampai yang sudah modern seperti mall yang
semakin banyak di bangun di Kota Malang.
Selain faktor di dari sektor industri dan
perdagangan faktor yang paling mempengaruhi adalah
bertambahnya penduduk yang menjadikan penduduk
memerlukan lahan untuk perumahan. Salah satu contoh
kongkritnya seperti di daerah Sumbersari dan daerah
Candi dulunya adalah lahan persawahan namun sekarang
ini telah berubah menjadi daerah pemukiman warga yang
sangat padat. Hal ini disebabkan oleh daerah ini
berdekatan dengan tempat-tempat pendidikan sehingga
warganya melihat potensi untuk dijadikan tempat kos dan
usaha di bidang kebutuhan bahan makan.
Faktor terpenting penyebab maraknya alih fungsi
tanah pertanian ke nonpertanian lainya adalah lemahnya
Law Enforcement (penegakan hukum) dalam pengendalian alih
fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Sebetulnya
pemerintah telah banyak membuat kebijakan untuk
pengendalian alih fungsi tanah pertanian, khususnya
tanah sawah sebagai tanah produksi padi. Akan tetapi
hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan
secara optimal, selain itu ditambah dengan lemahnya
koordinasi antara Departemen Pertanian, Dewan
Perencanaan Wilayah dengan pembuat kebijakan. Terkait
dengan itu, Nasoetion (2003) mengemukakan bahwa
setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi
alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan
sulit terlaksana, yaitu :
1. Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi
pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi
lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong
terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui
kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor
nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya
menggunakan tanah pertanian.
2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan
pengendaliah alih fungsi lahan baru menyebutkan
ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-
perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan
lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke
nonpertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan
lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara
individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-
peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang
dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.
3. Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW yang kemudian
dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi,
merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk
mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah
beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak
RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih
fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi
nonpertanian.
Sehubungan dengan tiga kendala di atas, tidak
efektifnya peraturan yang telah ada, juga dipengaruhi
oleh : (1) lemahnya sistem administrasi tanah; (2)
kurang kuatnya koordinasi antar lembaga terkait; dan
(3) belum memasyarakatnya mekanisme implementasi tata
ruang wilayah.
Dampak dari Perubahan Fungsi Lahan Pertanian di Kota
Malang
Alih fungsi lahan merupakan beralihnya fungsi
penggunaan lahan dari sektor pertanian ke sektor non
pertanian. Alih fungsi lahan tersebut secara langsung
mengurangi jumlah lahan pertanian yang ada di Kota
Malang. Dampak alih fungsi lahan pertanian antara lain
sistem ketahan pangan yang akan menjadi terganggu.
Secara umum di Kota Malang masih memiliki ketahanan
pangan yang baik. Dengan adanya alih fungsi lahan yang
sekarang ini banyak terjadi di daerah-daerah bukan
tidak mungkin Kota Malang yang tadinya surplus beras
menjadi kekurangan beras. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Widjanarko(2006) terkonsentrasinya
pembangunan perumahan dan industri di Pulau Jawa, di
satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor
nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri,
akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang
menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain:
a. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya
produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada
pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta
mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor
pertanian ke nonpertanian. Apabila tenaga kerja tidak
terserap seluruhnya akan meningkatkan angka
pengangguran.
b. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan
sarana pengairan menjadi tidak optimal
pemanfaatannya.
c. Berkurangnya ekosistem sawah di Jawa khususnya di
Kota Malang sedangkan pencetakan sawah baru yang
sangat besar biayanya di luar Pulau Jawa seperti di
Kalimantan Tengah, tidak menunjukkan dampak positif.
d. Bahwa alih fungsi lahan dapat menyebabkan
pengangguran-pengangguran baru di sektor pertanian,
hal ini dikarenakan pada waktu terjadi alih fungsi
lahan ke sektor non pertanian maka sebagian orang
akan kehilangan mata pencaharian baru. Sementara
sektor lain belum tentu dapat menerimanya karena
kurangnya keahlian yang ada.
d. Jumlah angka kemiskinan penduduk yang bekerja di
sektor pertanian mungkin dapat bertambah karena
adanya alih fungsi lahan. Ini terjadi karena sebagian
dari mereka akan kehilangan mata pencahariaanya
sehingga pendapatan mereka secara otomatis juga akan
hilang
Selain dampak tersebut dengan adanya alih fungsi
lahan dari sektor pertanian ke non pertanian juga bisa
menyebabkan timbulnya berbagai bencana seperti banjir,
tanah longsor, kekeringan. Ini dikarenakan kurangnya
daerah resapan air karena banyak berdirinya bangunan-
bangunan yang tadinya merupakan lahan pertanian.
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di
Kota Malang
Agar pengendalian terhadap upaya alih fungsi
lahan pertanian dapat efektif dan efisien di suatu
wilayah, Priyono(2011) memberikan strategi sebagai
berikut:
a. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang dibuat harus pro
rakyat, artinya kebijakan tersebut benar-benar
memperhatikan kepentingan rakyat, sehingga rakyat
merasa nyaman hidup dengan keluarganya maupun selalu
mau/memperhatikan ajakan pemerintah untuk menyukseskan
pembangunan, tidak mudah tergoda adanya hasrat untuk
mengkonversi tanah pertanian.
Kebijakan yang tidak berat sebelah contohnya yang
menyangkut perimbangan perolehan anggaran dari pusat
harus proporsional dapat ditinjau dari aspek potensi
sumberdaya (alam, energy, manusia), potensi rawan
keamanan, potensi kwalitas SDMnya, potensi geografis
wilayah, potensi rawan bencana, potensi pengembangan
IPTEKSnya, potensi pengembangan infrastruktur ekonomi
(pasar, sarana/prasarana transportasi, komunikasi dll).
Kebijakan disini benar-benar untuk rakyat, artinya
bukan hanya untuk kalangan pengusaha atau pegawai saja.
b. Instrumen Hukum
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal :
(1) .Mencabut sekaligus mengganti Peraturan perrundang-
undangan yang tidak sesuai kondisi kebutuhan petani
serta dengan mencantumkan sangsi yang tegas dan berat
bagi pelanggarnya; (2). Penerapan pengendalian secara
ketat khususnya tentang perijinan perubahan alih fungsi
lahan pertanian dan pengelolaannya harus sesuai RTRW;
(3). Menerapkan sangsi yang tegas dan berat bagi
pelanggarnya misal pelanggaran RTRW dll; (4).
Memberikan sangsi yang jauh lebih berat bagi
pelanggarnya dari kalangan aparat pemerintah/penegak
hukum antara lain yang menyangkut perijinan, perubahan
status tanah, dll; (5). Membuat Undang-Undang yang
memberikan jaminan kekuatan yang memadai dan sederajat
bagi organisasi petani dalam hubungannya
(memperjuangkan haknya) dengan fihak pemerintah dan
organisasi lain yang menyangkut setiap pengambilan
keputusan, khususnya yang menyangkut kebutuhan petani.
c. Instrumen Ekonomi
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal
pembuatan : (1). Kebijakan yang menyangkut jaminan
kestabilan harga dan keberadaan stok barang kebutuhan
petani; (2). Kebijakan yang menyangkut jaminan
kestabilan system distribusi (penyaluran) barang
kebutuhan petani; (3). Kebijakan yang menyangkut
jaminan social tenaga kerja (asuransi kerugian hasil
pertanian sepertti gagal panen atau anjloknya harga,
asuransi kecelakaan kerja pertanian, asuransi
pendidikan keluarga petani, asuransi kesehatan keluarga
petani dll); (4). Kebijakan yang menyangkut: pemberian
insentif setiap panen hasil pertanian bagi petani
penggarap atau buruh tani; dan pemberian desinsentif
bagi fiihak yang berminat dalam alih fungsi lahan
pertanian; (5). Kebijakan yang menyangkut pemberian
keringanan pajak khususnya sarana produksi pertanian
dan penjualan hasil pertanian dalam negeri.
d. Instrumen Sosial dan Politik
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal
pembuatan : (1) Kebijakan pemasyarakatan dan upayanya
pemakaian kembali produk alam Indonesia , khususnya
produk pertanian ke semua lapisan (seluruh) masyarakat;
(2) Kebijakan pemasyarakaran bahaya dan pencegahannya
dalam pembuatan dan pemakaian produk yang merugikan
kehidupan petani beserta keluarganya bahkan dapat
merusak lingkungan; (4) Pemeloporan secara pro aktif
gerakan penghijauan setiap jengkal tanah oleh
pemerintah dan tokoh/lembaga swadaya masyarakat;
(5).Pemeloporan gerakan secara pro aktif dan
pembentukan satgas sadar lingkungan dimulai dari RT
hingga ke pusat.
e. Instrumen Pendidikan dan IPTEKS
Perlu diupayakan secara kongkrit dalam hal
penerapan : (1). Pemberian pen-didikan bermoral bangsa
Indonesia, ilmu, ketrampilan dan seni yang me-madai dan
efektif tentang pengelolaan usaha pertanian yang
prospektif yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati bagi
konsumen; dan (2) .Pemberian ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna yang sesuai dan terjangkau oleh
kemampuan petani seperti budidaya tanaman hias,
sayuran, dan sebagainya di lahan sempit.
Dengan adanya strategi-strategi ini diharapkan
Kota Malang dapat mempertahankan lahan pertanian
sehingga tidak berubah fungsinya. Selain itu,
swasembada pangan juga terus terjamin baik untuk
memenuhi kebutuhan di Kota Malang sendiri maupun daerah
lain dan tanaman-tanaman pertanian tidak akan punah.
Berkaitan dengan infiltrasi, diharapkan semakin banyak
daerah peresapan air sehingga banjir yang biasanya
menjadi masalah serius di Kota Malang akan teratasi.
Kesimpulan
Dari Hasil penelitian, dapat dapat diketahui
bahwa lahan pertanian adalah lahan yang ditunjukan atau
cacok untuk di jadikan lahan usaha tani untuk
memproduksi tanaman pertanian. Sedangkan Alih fungsi
lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan
adalah diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan
lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis
besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan
penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan
meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih
baik.
Di Kota Malang sendiri tidak luput dari adanya
perubahan fungsi lahan lahan pertanian. Alih fungsi
lahan banyak terjadi di daerah Klojen. Namun daerah-
daerah lain seperti Kedungkandang, Lowokwaru, Sukun,
dan Blimbing juga sudah menunjukan alih fungsi lahan
yang pesat. tahun 2007 luas lahan pertanian di daerah
itu mencapai 1.550 hektar, tahun 2009 menyusut menjadi
1.400 hektar dan tahun ini tinggal 1.300 hektare
Berkembangnya perumahan, sektor industri dan pariwisata
yang tidak dapat dibendung menjadi penyebab utama alih
fungsi lahan di daerah ini.
Faktor yang paling mempengaruhi pengalihan fungsi
lahan pertanian di Kota Malang antara lain pertumbuhan
pada sektor perekonoman dan industri yang membutuhkan
banyak lahan untuk melakukan kegiatannya. Banyak sekali
bangunan yang dibangun untuk pabrik-pabrik dan
pertokoan. Selain itu bertambahnya penduduk yang
menjadikan penduduk memerlukan lahan untuk perumahan
semakin banyak . Salah satu contoh kongkritnya seperti
di daerah Sumbersari dan daerah Candi dulunya adalah
lahan persawahan namun sekarang ini telah berubah
menjadi daerah pemukiman warga yang sangat padat.
Faktor terpenting penyebab maraknya alih fungsi tanah
pertanian ke nonpertanian lainya adalah lemahnya Law
Enforcement (penegakan hukum) dalam pengendalian alih fungsi
tanah pertanian ke non pertanian. Sebetulnya pemerintah
telah banyak membuat kebijakan untuk pengendalian alih
fungsi tanah pertanian untuk implementasinya belum
berhasil diwujudkan secara optimal sebab lemahnya
koordinasi dari pemerintah sendiri.
Dampak dari adanya perubahan fungsi lahan ini
adalah Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan
turunnya produksi padi, yang lambat lau akan mengganggu
tercapainya swasembada pangan dan timbulnya kerawanan
pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja
dari sektor pertanian ke nonpertanian; Investasi
pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana
pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
Berkurangnya ekosistem sawah di Jawa; pengangguran-
pengangguran baru di sektor pertanian dan Jumlah angka
kemiskinan penduduk yang bekerja di sektor pertanian
mungkin dapat bertambah karena adanya alih fungsi lahan
ini. Hal ini terjadi karena sebagian dari mereka akan
kehilangan mata pencahariaanya sehingga pendapatan
mereka secara otomatis juga akan hilang. Selain itu,
alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non
pertanian juga bisa menyebabkan timbulnya berbagai
bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Ini
dikarenakan kurangnya daerah resapan air karena banyak
berdirinya bangunan-bangunan yang tadinya merupakan
lahan pertanian.
Strategi yang diterapkan untuk mencegah
terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian di Kota
Malang antara lain pemerintah harus menetapkan
Kebijakan yang pro rakyat dan tidak berat, Penerapan
pengendalian secara ketat khususnya tentang perijinan
perubahan alih fungsi lahan pertanian dan
pengelolaannya, Kebijakan yang menyangkut jaminan
kestabilan harga dan keberadaan stok barang kebutuhan
petani, memeloporan secara pro aktif gerakan
penghijauan setiap jengkal tanah oleh pemerintah dan
tokoh/lembaga swadaya masyarakat dan Pemberian ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang sesuai dan
terjangkau oleh kemampuan petani. Dengan adanya
strategi-strategi ini diharapkan Kota Malang dapat
mempertahankan lahan pertanian sehingga tidak berubah
fungsinya
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang
ada maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan pencatatan secara sistematis
mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang
terjadi melalui perangkat perangkat desa dan dapat
secara jelas diketahui seberapa besar kegiatan
tersebut telah terjadi sehingga dapat dilakukan
penanggulangan secara tepat terhadap kegiatan alih
fungsi lahan yang marak terjadi.
2) Melakukan upaya intensifikasi pertanian agar lahan
dapat berproduksi secara optimal sehingga
keberlangsungan usaha pertanian dapat terus
berlangsung sehingga kebutuhanakan pangan (beras) dan
kesejahteraan petani dapat terjamin.
3) Perlu adanya sosialisasi mengenai perundang-undangan
tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan
secara tegas terhadap pelanggaran, mengingat hal
tersebut dapat berdampak pada stabilitas nasional
mengenai pengadaan pangan yang sifatnya sangat vital.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistika. 2004. Statistik Indonesia. Jakarta:Badan Pusat Statistik Indonesia.
Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. StrategiPengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian BertumpuPada Partisipan Masyarakat. Pusat Analisis SosialEkonomi dan Kebikjakan Pertanian. Bogor.
Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak dan PolaPemanfaatannya. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomidan Kebijakan Pertanian.
Kecamatan Lowokwaru. 2014. Profil Kec. Lowokwaru.(Online)(http://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/) diakses 10 Oktober 2014.
Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian BagiTaraf Hidup Petani. Skripsi. Bogor. InstitutPertanian Bogor. (Online)(http://kolokiumkpmipb.wordpress.com) diakses 10 Oktober 2014.
Nasoetion, L.I. 2003. Konversi Lahan Pertanian : AspekHukum dan Implementasinya. Dalam Kurnia dkk.(eds). Makalah Seminar Nasional “MultifungsiLahan Sawah dan Konversi Lahan Pertanian”.Pusat Penelitian dan Pengembangan TanahdanAgroklimat, Badan Penelitian danPengembangan Pertanian. Bogor.
Priyono. 2011. Alih Fungsi Lahan Pertanian Merupakan SuatuKebutuhan Atau Tantangan. Bengkulu: ProsidingSeminar Nasional Budidaya Pertanian.
Sukarelawati, Endang. 2012. Lahan Pertanian di KotaMalang Terus Menyusut. (Online)(https://www.google.com/search?q=%2FLahan+Pertanian+di+Kota+Malang+Terus+Menyusut+++ANTARA+JATIM++
+Portal+Berita+Daerah+Jawa+Timur.htm&ie=utf-8&oe=utf-) diakses 10 oktober 2014.
Sumaryanto, Syahyuti, Saptana dan B. Irawan. 2007. Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria. Forum Penelitian AgroEkonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Wibowo, S.C. 1996. Analisis Pola Konversi Sawah SertaDampaknya Terhadap Produksi Beras : Studi Kasus di JawaTimur. Bogor: Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian,Institut Pertanian Bogor.
Winoto, J. 2005. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi TanahPertanian dan Implementasinya. Makalah Seminar“Penanganan Konversi Lahan danPencapaian LahanPertanian Abadi”, Kerjasama Kantor KementerianKoordinator Bidang Perekonomian dengan PusatStudi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan(Institut Pertanian Bogor). Jakarta.
Witjaksono, 2006. Alih Fungsi Lahan : Suatu Tinjauan
Sosiologis. Prosiding Lokakarya Persaingan dalamPemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air. PusatPenelitian dan Pengembangan Sosial EkonomiPertanian dan Ford Foundation.