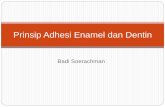PEMENUHAN PRINSIP ETIKA LINGKUNGAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK GIANT SEA WALL DI TELUK JAKARTA
Transcript of PEMENUHAN PRINSIP ETIKA LINGKUNGAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK GIANT SEA WALL DI TELUK JAKARTA
PEMENUHAN PRINSIP ETIKA LINGKUNGAN DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN PROYEK GIANT SEA WALL DI TELUK JAKARTA
Abstrak
Lingkungan Hidup harus menjadi bagian integral dalam keseluruhan kebijakan pembangunan. Salah satu alat dalam pelaksanaannya adalah peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan ini menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara negara dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup. Keseriusan dalam menjaga lingkungan hidup menuntut adanya komitmen moral pemerintah dalam mematuhi berbagai ketentuan formal dan kebijakan yang pro lingkungan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersepakat untuk membangun Giant Sea Wall 'Tanggul Raksasa' yang termasuk ke dalam program National Capital Intergrated Coastal Development (NCICD). Nantinya pembangunan Giant Sea Wall ini meliputi 3 tahapan.
Rencana pembangunan Giant Sea Wall dalam rangka penanggulangan banjir di teluk Jakarta menimbulkan banyak pro dan kontra. Disinyalir pula bahwa rencana pembangunan tersebut belum memperhatikan kaidah-kaidah pemenuhan etika lingkungan hidup dengan tidak menyertakan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rencana masterplannya namun prosesnya terus berlanjut hingga proses ground breaking pertama. Selain itu izin pembangunan proyek ini juga diterbitkan tanpa pertimbangan objektif yang memadai yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Etika lingkungan hidup tidak hanya membahas mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan, serta berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap alam.
Keywords: etika, lingkungan, pemerintah, giant sea wall.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pembangunan fisik yang pesat saat ini khususnya di kawasan perkotaan
meninggalkan permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan bersama,
permasalahan ini berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan yang kurang
memperhatikan aspek etika. Secara Etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu
ethos yang berarti ‘adat-istiadat’ atau kebiasaan. Dalam arti ini etika berkaitan dengan
kebiasaan hidup yang baik dalam masyarakat. Etika kemudian sering dipahami sebagai
ajaran atau perintah tentang baik-buruk, dalam definisi ini etika sering dikaitkan dengan
perilaku moral. Jika kemudian dipahami secara luas, etika bukan sekedar pelajaran
tentang baik-buruk dalam hal perilaku manusia, tetapi juga dapat berlaku bagi sebuah
entitas besar yaitu dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kehidupan bernegara.
Etika pembangunan melihat pembangunan sebagai sebuah bidang multidisiplin dimana
teori dan praktik berjalan dalam berbagai sudut pandang, lebih lanjut etika pembangunan
berupaya memahami sifat alamiah, sebab-sebab, dan akibat-akibat pembangunan bagi
perubahan sosial.
Lingkungan Hidup harus menjadi bagian integral dalam keseluruhan kebijakan
pembangunan. Salah satu alat dalam pelaksanaannya adalah peraturan perundang-
undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan ini menjadi pegangan bagi setiap
penyelenggara negara dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup.
Keseriusan dalam menjaga lingkungan hidup menuntut adanya komitmen moral
pemerintah dalam mematuhi berbagai ketentuan formal dan kebijakan yang pro
lingkungan.
Jakarta sebagai ibukota negara memiliki posisi daratan lebih rendah daripada
permukaan laut, kondisi ini menyebabkan pesisir kota Jakarta menjadi langganan banjir
akibat naiknya permukaan air laut. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah pusat
bersama pemerintah daerah berencana membangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta.
Giant sea wall adalah sebuah tanggul laut raksasa yang membentengi Teluk Jakarta.
Proyek dengan panjang 30 kilometer dan bernilai di atas Rp 200 triliun tersebut
dirancang untuk mengatasi banjir akibat kenaikan permukaan air laut, membersihkan air
sungai sebelum ke laut, dan reklamasi pantai. Rencana pembangunan tanggul raksasa
dalam rangka penanggulangan banjir di teluk Jakarta (Giant Sea wall) menimbulkan
banyak pro dan kontra.
Pihak yang kontra menyatakan tanggul laut raksasa akan memperparah banjir di
Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kehadiran tanggul laut akan memperpanjang alur sungai
sehingga memperlambat aliran air dan peningkatan laju sedimentasi karena menurunnya
kecepatan aliran air. Dengan demikian, selain banjir juga terjadi percepatan pendangkalan
sungai yang perlu biaya pengerukan rutin besar. Di sisi lain terjadi penutupan yaitu
penutupan dua pelabuhan perikanan Nusantara sehingga ribuan nelayan harus
dipindahkan. Pembangkit Listrik Muara Karang juga harus ditutup karena aliran air
pendingin tidak lagi tersedia. Jikalau dipertahankan, biaya operasinya sangat besar karena
memerlukan pompa yang berjalan terus. Tanggul laut raksasa yang direncanakan dalam
sistem tertutup membuat air tidak mengalir dan pada akhirnya, akan menyebabkan
kualitas lingkungan Laut Jakarta akan rusak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
bersepakat untuk membangun Giant Sea Wall 'Tanggul Raksasa' yang termasuk ke dalam
program National Capital Intergrated Coastal Development (NCICD). Nantinya
pembangunan NCICD ini meliputi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pembangunan
tanggul eksisting. Tahap kedua adalah pembangunan konsep grade Garuda. Tahap ketiga
adalah pembangunan pesisir sebelah timur.
Disinyalir pula bahwa rencana pembangunan tersebut belum memperhatikan
kaidah-kaidah pemenuhan etika lingkungan hidup dengan tidak menyertakan analisis
dampak lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam
rencana masterplannya namun prosesnya terus berlanjut hingga proses ground breaking
pertama. Izin pembangunan proyek ini juga diterbitkan tanpa pertimbangan objektif yang
memadai yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Etika lingkungan hidup dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus
dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan – pilihan moral yang terkait dengan isu
lingkungan hidup. Selain itu, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan
moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup dan
apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang
berdampak pada lingkungan hidup termasuk dalam etika ini. Sehingga, etika lingkungan
hidup tidak hanya membahas mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga
mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan
manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup
lain atau dengan alam secara keseluruhan, serta berbagai kebijakan politik dan ekonomi
yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap alam .
B. Tujuan
Makalah ini akan membahas rencana pembangunan Giant Sea Wall di Teluk
Jakarta yang merupakan bagian dari proyek NCICD dalam perspektif etika
pembangunan yang mencakup etika lingkungan hidup dan etika pemerintah sebagai
pengelola dan pembuat kebijakan lingkungan hidup yang baik.
C. Metodologi
Makalah ini dilakukan bersifat deskriptif evaluatif yaitu menyusun dan
mendeskripsikan kondisi Proyek Giant Sea Wall yang merupakan bagian dari NCICD di
Teluk Jakarta, membandingkan kemudian menilai kesesuaiannya dengan teori etika
pembangunan yang ideal. Data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana akan
dilakukan studi literatur dari berbagai sumber dan pengumpulan data sekunder mengenai
Giant Sea Wall dalam proyek NCICD.
BAB II
TINJAUAN LITERATUR
A. Etika secara umum
Secara teoritis etika mempunyai pengertian, sebagai berikut: Pertama: secara
etimologis, Etika berasal dari kata Yunani yaitu Ethos yang berarti adat istiadat atau
kebiasaan. Dalam pengertian luas, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata
cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun masyarakat. Kebiasaan hidup
yang baik ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi lalu dibakukan dalam
bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami dan diajarkan
secara lisan dalam masyarakatt. Singkatnya kemudian etika dipahami sebagai ajaran yang
berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia. Adanya kaidah
atau norma ini bertujuan untuk mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu
yaitu apa yang dianggap baik dan penting di dalam masyarakat. Pengertian etika yang
seperti ini terkadang rancu dengan apa yang disebut moralitas. Jika dipahami berbeda
dengan moralitas, maka etika adalah refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus
hidup dan bertindak dalam situasi konkret tertentu. Refleksi kritis yang dimaksud adalah
ketentuan untuk menentukan sikap, pilihan dan bertindak secara benar sebagai manusia.
B. Etika dan pembangunan
Pembangunan seringkali didefinisikan sebagai seperangkat usaha yang terencana
dan terarah untuk menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia. Dalam pembangunan diperlukan modal yaitu keseluruhan
sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan dalam proses pembangunan. Selain itu
pembangunan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara
bijaksana. Perkembangan etika pembangunan diawali dari penilaian yang dilakukan oleh
para ahli dan praktisi pembangunan terhadap teori-teori dan praktek-praktek
pembangunan. Dalam hal ini etika dan nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori,
perencanaan dan praktek pembangunan karena pembangunan akan kehilangan makna
jika mengorbankan kemanusiaan. Etika pembangunan cenderung melihat pembangunan
sebagai bidang multi disiplin dimana komponen teori dan praktek berjalan dalam
beberapa cara, dalam etika pembangunan tidak hanya berusaha memahami sifat alamiah,
sebab-sebab dan juga akibat-akibat pembangunan tetapi juga perubahan sosial apa yang
akan terjadi dan apakah perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang baik.
Masuknya konsep etika dalam proses pembangunan melahirkan teori dan praktek
baru dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai contoh lahirnya prinsip pembangunan
yang berkelanjutan. Pada awalnya teori pembangunan hanya menitikberatkan kepada
aspek fisik dan pengembangan ekonomi sehingga lahirlah teori-teori pembangunan
terpusatkan dan mobilisasi modal, pembangunan berimbang, pembangunan pemertaan,
dsb. Namun saat ini, mulai disadari bahwa pembangunan tidak hanya persoalan ekonomi
tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan generasi selanjutnya untuk itulah
kemudian muncul teori pembangunan berkelanjutan. Dua gagasan penting dalam teori
pembangunan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia
khususnya dalam hal ini kaum miskin dan gagasan mengenai keterbatasan sumber daya
alam untuk memenuhi kebutuhan dimasa kini ataupun dimasa mendatang. Pembangunan
berkelanjutan mencakup tiga dimensi pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan
lingkungan hidup. Karakteristik dari pembangunan berkelanjutan adalah menjamin
pemerataan dan keadilan; menghargai keanekaragaman hayati; menggunakan pendekatan
integratif dan menggunakan pandangan jangka panjang.
Prinsip baru ini kemudian melahirkan nilai-nilai tentang apa yang boleh dan apa
yang tidak boleh dilakukan dalam proses pembangunan, seperti telah dijabarkan
sebelumnya nilai-nilai tentang bagaimana bersikap inilah yang disebut etika. Etika dan
pembangunan tidak dapat terlepas satu dan lainnya, tidak hanya menyesuaikan dengan
prinsip-prinsip pembangunan tertentu seperti pembangunan berkelanjutan, tetapi
merupakan suatu hal yang sudah seharusnya menjadi bagian dalam proses pembangunan.
Pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan etika akan menghasilkan produk
pembangunan yang tidak patut dalam masyarakat.
C. Etika lingkungan
Isu lingkungan saat ini menjadi sebuah isu politik yang global, lingkungan hidup
bukan semata-mata persoalan teknis tetapi juga terdapat persoalan moral didalamnya.
Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini
baik pada lingkup global maupun lingkup nasional sebagian besar bersumber dari
perilaku manusia. Krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan
melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Dibutuhkan
sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang
tetapi juga budaya masyarakat akhir tahun secara keseluruhan. Pada titik inilah
dibutuhkan etika lingkungan hidup.
Etika lingkungan hidup disini dipahami sebagai bagian dari kaidah atau norma
yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip
moral yang menjiwai perilaku manusia daalam berhubungan dengan alam tersebut. Lebih
luas etika lingkungan tidak hanya berbicara soal perilaku manusia terhadap alam tetapi
juga berbicara mengenai relasi diantara semua kehidupan alam semesta yaitu antara
manusia dengan manusia yang berdampak pada alam dan antara manusia dengan
makhluk hidup lain, termasuk di dalamnya kebijakan politik atau ekonomi yang
mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam. Etika lingkungan hidup
memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya yaitu:
1. Sikap hormat terhadap alam
Hormat terhadap alam merupakan prinsip dasar manusia sebagai bagian dari alam
semesta, seperti halnya kewajiban dalam suatu komunitas sosial yang mempunyai
kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama. Dengan kata lain, alam mempunyai hak
untuk dihormati tidak hanya karena manusia hidup bergantung pada alam tetapi karena
kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam, manusia adalah
bagian dari komunitas ekologis.
2. Prinsip Tanggung Jawab
Kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta melahirkan sebuah
prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta
seluruhnya dan integritasnya maupun terhadap keberadaan dan kelestarian setiap bagian
dan benda di alam semesta ini, khususnya makhluk hidup. Tanggung jawab ini tidak
hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Prinsip tanggung jawab ini menuntut
manusia untuk mengambil prakarsa, usaha kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata
untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Wujud konkretnya semua orang harus
bisa menjaga dan melestarikan alam serta mencegah atau memulihkan kerusakan yang
timbul. Tanggung jawab ini terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang atau
menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak sengaja merusak atau
membahayakan keseimbangan lingkungan.
Masalah lingkungan hidup dapat disoroti juga dari sudut keadilan sosial. Pelaksanaan
keadilan individual semata-mata tergantung pada kemauan baik atau buruk dari individu
tertentu. Secara tradisional keadilan sosial hampir selalu dikaitkan dengan kondisi kaum
buruh dalam industrialisasi abad ke-19 dan ke-20. Pelaksanaan keadilan di bidang
kesempatan kerja, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal yang sejenis
berlaku juga dalam konteks lingkungan hidup. Contohnya jika di Eropa, satu perusahaan
memutuskan untuk tidak lagi membuang limbah industrinya ke dalam laut utara, kualitas
air laut dan keadaan flora dan faunanya hampir tidak terpengaruhi, selama terdapat ribuan
perusahaan di kawasan itu yang tetap mencemari laut dengan membuang limbahnya.
Kini sudah tampak beberapa gejala yang menunjukkan bagaimana lingkungan
hidup memang mulai disadari sebagai suatu masalah keadilan sosial yang berdimensi
global. Sudah terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif di bidang lingkungan
hidup di banyak negara. Di beberapa Negara di Eropa Barat juga terdapat partai politik
yang memiliki sebagian program pokok memperjuangkan kualitas lingkungan hidup.
Walaupun di bidang lingkungan hidup sebagai masalah keadilan sosial para individu
masing-masing tidak berdaya, itu tidak berarti bahwa manusia perorangan sebaiknya
hanya diam saja. Keadilan sosial dalam konteks lingkungan hidup lebih mudah terwujud
dengan kesadaran atau kerja sama semua individu, daripada keadilan sosial pada taraf
perburuan, karena pertentangan kelas dan kepentingan pribadi yang tidak begitu tajam.
Masalah lingkungan hidup menyangkut masa depan kita semua. Jika ada kesadaran
umum, bersama-sama akan dicapai banyak kemajuan ekologis.
D. Etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik
dalam perjalanan roda pemerintahan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian visi dan misi secara efektif dan
efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem
kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan
penyelenggaraan pemerintahan bisa dicapai dan diwujudkan. Paradigma penyelenggaraan
pemerintahan yang benar adalah pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan
kehendak dan aspirasi masyarakat demi menjamin kepentingan masyarakat terpenuhi.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu dapat mensyaratkan beberapa hal:
1. Dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik pemerintah itu sendiri harus
benar-benar efektif dalam memerintah. Karena apabila selama menjalankan
pemerintahan, pemerintah tidak efektif dan lemah kekuasaan, maka pemerintah akan
menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan. Hal ini menyebabkan
penyelenggaraan pemerintahan dibelokkan dari esensinya yang benar untuk melayani
kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Untuk
memenuhi persyaratan ini pemerintah harus kuat, kuat disini berarti mampu melawan
berbagai politik kepentingan sempit yang bermaksud menyelewengkan kepentingan
pemerintahan itu sendiri.
2. Prasyarat berikutnya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik pemerintah harus
tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Ini berarti penyelenggaraan pemerintahan
harus benar-benar menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Hanya dengan
jalan ini, ada aturan main yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bersama dalam
menyelenggarakan kehidupan bersama yang menjamin kepentingan bersama. Tanpa
kepatuhan terhadap hukum ini oleh penyelenggara pemerintahan, maka akan sulit
terjadinya kepastian hukum. Akibatnya sistem penyelenggaraan pemerintah akan menjadi
rusak sehingga mustahil tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Keadilan Sosial
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selain menjadi subjek
pemerintah juga dapat berperan sebagai wasit dan penjaga aturan hukum yang ada demi
menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Pemerintah harus menjadi pihak yang
netral dengan memperlakukan semua orang dan kelompok secara sama dan berdasarkan
hukum yang berlaku, sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dari pemerintah
terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan jalan ini maka pemerintah dapat
menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan sehingga terselenggara pemerintahan yang
baik sebagaimana yang dicita-citakan.
Prinsip-prinsip tersebut harus terlihat dalam penyelenggaraan pemertintahan yang
baik, ada hubungan yang sangat erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dengan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada korelasi sangat positif terkait
keduanya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan
menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Tanpa penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sulit untuk mewujudkan adanya pengelolaan lingkungan yang
baik, komitmen ini sangat dibutuhkan karena pemerintah dapat bertindak sebagai subjek,
objek atau bahkan pengawas dalam pengelolaan lingkungan. Setiap tindakan yang
diambil pemerintah akan membawa dampak luas bagi bangsa dan negara. Dalam
melaksanakan prinsip etika ini pemerintah menterjemahkan ke dalam penyusunan
berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan dalam penegelolaan
lingkungan hidup dan diaplikasikan ke dalam berbagai kebijakan operasional.
BAB III
UNSUR
A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah No. 29 Tahun 1986. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami
beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23
Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya
dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka
PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999,
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27
Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.
Dalam PP No. 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan / atau kegiatan. Hal ini juga tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) No.32 Tahun 2009, pasal 1 ayat 11.
Dalam UUPPLH pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap usaha dan / atau
kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan / atau
kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
e. sifat kumulatif dampak
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak ; dan/atau
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kriteria usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi
dengan amdal terdiri atas:
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,
lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan
konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggidan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup
B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dalam UUPPLH No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah daerah
wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau
kebijakan, rencana, dan / atau program. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan / atau
kerusakan lingkungan hidup. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan
hidup di suatu wilayah
b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan rencana, dan / atau program
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
KLHS memuat kajian antara lain :
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
c. Kinerja layanan / jasa ekosistem
d. Efisiensi pemanfaat sumber daya alam
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
C. Master Plan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
Selama beberapa tahun pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah
bekerja bersama-sama untuk mengurangi dan mencegah banjir di Ibukota Negara
Indonesia. Kerjasama ini telah menghasilkan Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)/
Strategi Pertahanan Pesisir Jakarta (SPPJ) pada 2001. Kerja sama bilateral ini diteruskan
pada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) /
Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Proyek ini memakan biaya
sekitar 600 triliun.
Proyek Masterplan NCICD ini merupakan pengembangan dari dikembangkan di
bawah bimbingan langsung dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan merupakan hasil kerja sama jangka panjang antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda di bidang pengelolaan air. Tujuan utama
Master Plan NCICD ini adalah untuk memberi perlindungan jangka panjang untuk
Jakarta dari banjir dari sungai dan air laut, dan di saat yang bersamaan Master Plan ini
akan memfasilitasi pengembangan sosio-ekonomi Jakarta.
Terdapat 3 (tiga) tipe banjir di Ibukota Jakarta. Yang pertama, hujan lebat di kota
yang dikombinasikan dengan kapasitas penyimpanan air yang tidak mencukupi telah
menghasilkan genangan. Karena curah hujan yang berlebihan di kota ini mengalir kearah
wilayah pesisir yang berdataran rendah, daerah inilah yang paling rentan terhadap banjir
tipe ini. Tipe banjir kedua datang dari sungai-sungai dan kanal-kanal sebagai akibat
tingginya laju aliran di hulu. Pada banyak tempat kapasitas sistem air saat ini tidak
mencukupi. Tanggul sungai tidak cukup tinggi atau cukup kuat dan sungai-sungai, anak
sungai dan pompa tersumbat oleh sedimen dan sampah. Akibatnya sungai-sungai ini
meluap. Tipe banjir ketiga datang dari laut ketika tanggul laut, dan tanggul sungai di
daerah pesisir, tidak cukup tinggi atau cukup kuat. Ketika laut berada di muka air
tertinggi, tanggul-tanggul ini terlimpasi, dan air laut membanjiri kota ini seperti yang
terjadi pada tahun 2007.
Master Plan ini bermaksud untuk mencegah tipe ketiga banjir. Saat ini tipe ketiga
banjir ini sangat mungkin terjadi karena pertahanan banjir Jakarta sudah tidak mencukupi
lagi. Survey pendahuluan dari 2013 memperlihatkan bahwa saat ini lebih 40% pertahanan
banjir di daerah pantai tidak mampu menahan muka air laut tertinggi. Untuk mengatasi
banjir tipe banjir ketiga ini, pemerintah DKI Jakarta merencanakan membangun Tanggul
Raksasa. (Giant Sea Wall)
Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) ini akan dibangun sepanjang 37 - 40km mulai
dari Bekasi hingga Tangerang, dan dibagi ke dalam 3 (tiga) fase. Fase Pertama yaitu
revitalisasi pesisir yang terdiri dari penguatan tanggul laut dan tanggul sungai yang ada,
yang perlu untuk mempertahankan Jakarta dalam kondisi aman selama beberapa tahun ke
depan. Fase ditargetkan selesai pada tahun 2017. Fase kedua adalah terdiri atas penutupan
bagian barat Teluk dengan Tanggul Laut Luar. Dibagian barat Jakarta penurunan muka
tanah ini tertinggi, yang membuat penutupan bagian barat teluk ini menjadi yang paling
diperlukan. Pembangunan konstruksi tanggul terluar ini dengan tembok bergambar
garuda raksasa di laut dalam. Penutupan bagian timur teluk ini (Fase Ketiga) hanya
diperlukan jika usaha untuk memperlambat atau menghentikan penurunan muka tanah di
bagian timur tidak berhasil. Ini akan menjadi pengembangan jangka panjang yang
tergantung pada hasil-hasil pemantauan. Fase ketiga ini disebut dengan Jakarta Giant Sea
Wall / Tanggul Raksasa yang proses ground breaking-nya sudah dilaksanakan pada
Oktober 2014. Sementara fase pertama dan fase kedua dilaksanakan secara paralel
dengan proses konstruksi fase ketiga.
Menurut Kajian Awal Proyek Giant Sea Wall akan menyebabkan beberapa
dampak lingkungan. Dampak Lingkungan yang akan muncul ini adalah :
Hutan Bakau
Penutupan teluk ini akan mempercepat degradasi hutan bakau. Teluk ini akan
berubah menjadi waduk air tawar dengan keadaan hidrolik yang berbeda, yang
membuat hutan bakau tidak mungkin berkompetisi dengan spesies lain yang toleran
terhadap air yang kurang asin. Hutan bakau air payau yang tersisa akan berubah
menjadi habitat air tawar.
Mutu Air
Penutupan teluk ini membuat pembersihan sungai-sungai menjadi keharusan.
Penutupan ini menciptakan momentum untuk melaksanakan upaya-upaya sanitasi
dan karenanya mempunyai dampak positif terhadap mutu air. Di samping itu juga,
pelaksanaan ini mempunyai pengaruh positif terhadap keadaan kehidupan di
sepanjang sungai-sungai dan garis pantai. Peningkatan mutu air mempengaruhi
pengaruh positif terhadap ekosistem laut dan memungkinkan peningkatan
produktivitas perikanan.
Kehidupan laut
Penutupan teluk ini akan mengubah Teluk Jakarta menjadi danau retensi air tawar
yang memiliki dampak besar terhadap keadaan ekologis Teluk Jakarta. Spesies laut
yang menetap, jenis ikan dan benthos akan musnah.
Mega proyek NCICD ini juga secara inheren penuh resiko. Ukuran proyek,
kompleksitas dan durasi menciptakan berbagai resiko teknis, keuangan dan organisasi.
Tiga risiko besar proyek NCICD adalah:
Pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang yang tidak menentu.
Penurunan sementara pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada harga real estat
dan akibatnya pada kasus bisnis dan dalam kasus terburuk, kecepatan realisasi
Garuda Megah.
Ketersediaan pasir. Ada permintaan besar pasir untuk reklamasi lahan, tetapi hanya
daerah sumber terbatas. Harga pasir dan biaya transportasi bisa dengan mudah naik
apabila pasir harus didatangkan dari daerah sumber yang jauh
Kualitas Air. Upaya untuk membersihkan air drainase perkotaan dengan
pembangunan sistem saluran dan pengolahan air limbah harus dipercepat secara
signifikan. Namun, ini bukan tugas yang mudah di kota yang berpenduduk padat.
Jika kualitas air tidak membaik, kualitas air di waduk akan buruk., mempengaruhi
baik penduduk dan potensi pasar Garuda Megah dan menghalangi penggunaan
waduk sebagai sumber pasokan air baku.
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Permasalahan Pembangunan Giant Sea Wall dalam proyek NCICD
Giant Sea Wall ini belum memenuhi persyaratan teknis berupa dokumen Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
AMDAL ini sangat penting karena merupakan kajian mengenai dampak besar yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang proyek ini, sedangkan KLHS ini penting karena dokumen ini memuat rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
Giant Sea Wall.
Beberapa ahli menyatakan pembangunan tanggul akan berakibat terhadap kualitas
air di dalam tanggul akan memburuk secara progresif. Hal ini ditandai dengan perubahan
signifikan parameter lingkungan, seperti kenaikan biological oxygen demand (BOD)
lebih dari 100 persen, penurunan dissolved oxygen (DO) lebih dari 20 persen, dan
penurunan salinitas air lebih dari 3 persen. Selain itu pembangunan ini menyebabkan
adanya penutupan dua pelabuhan perikanan Nusantara, sehingga ribuan nelayan harus
dipindahkan dan pembangkit listrik Muara Karang juga harus ditutup karena aliran
pendingin tidak tersedia.
Terkait dengan pembangunan tersebut, timbulnya kritik dari beberapa aktivis
lingkungan dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang menganggap pembangunan Giant Sea Wall (GSW) tersebut tidak
berpihak pada lingkungan hidup. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
mengungkapkan bahwa ada banyak dampak yang muncul akibat pembangunan GSW di
Teluk Jakarta bagi nelayan. Beberapa dampak yang akan muncul akibat pembangunan
GSW di Teluk Jakarta bagi para nelayan :
1. Pembangunan GSW ini dinilai tidak layak secara aspek antara lain aspek lingkungan,
ekonomi dan sosial. Pemerintah selama ini terindikasi tidak membuka informasi kepada
publik. Bahkan pemerintah juga tidak pernah mengajak berdiskusi atau diberikan
informasi kepada masyarakat nelayan di Jakarta Utara yang nantinya akan terdampak
oleh proyek itu. Pembangunan GSW hanya diperuntukkan bagi kalangan elite saja.
Berikut adalah tabel dampak pembangunan Giant Sea Wall dalam proyek NCICD di
Teluk Jakarta bagi beberapa nelayan berdasarkan sumber data dan informasi Kiara antara
lain :
2. Dampak terhadap lingkungan adalah banyaknya ekosistem yang akan rusak contohnya
hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem tersebut penentu
produksi perikanan karena berperan sebagai spawning ground, nursery ground, dan
feeding ground. Kehilangan itu semua akan berdampak pada sangat berkurangnya hasil
tangkapan nelayan. Mangrove dan Padang lamun juga merupakan penangkap karbon
yang andal melebihi hutan darat sehingga kehilangannya dapat membuat pemerintah
tidak mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 % tanpa bantuan asing
3. Mengorbankan perempuan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga
nelayan dalam membantu mengolah ikan secara tradisional.
4. Sumber daya ikan yang hilang dari pesisir membuat nelayan harus melaut jauh dari
pantai sehingga memakan biaya sangat tinggi dan juga sangat berisiko dalam hal
keselamatan melaut.
B. Pelanggaran Giant Sea Wall terhadap Prinsip-prinsip Etika
Pembangunan NCICD ini terbagi dalam tiga tahap, yakni tipe A, B, dan C.
NCICD tipe A merupakan proyek reklamasi pulau ditambah dengan peninggian tanggul
rob setinggi 5 kilometer di bibir pantai utara sepanjang 63 kilometer, yang membentang
di sepanjang Teluk Jakarta, dari Tangerang hingga Bekasi.Kemudian, tipe B ialah
pembangunan konstruksi tanggul terluar dengan tembok bergambar garuda raksasa di laut
dalam, sedangkan tipe C ialah pembangunan Jakarta Giant Sea wall (GSW) atau yang
dikenal dengan Tanggul Raksasa. Proyek pembangunan Giant Sea Wall alias Tanggul
Raksasa Jakarta terus menjadi perdebatan. Awalnya, pemerintah bakal membangun
bendungan itu pada tahun ini. Namun karena berbagai permasalahan yang muncul,
mengakibatkan pengerjaan mega proyek itu tertunda.
Peletakan batu pertama pembangunan GSW telah dilakukan pada tanggal 9
Oktober 2014 lalu, dan diresmikan secara langsung oleh Menteri Koordinator
Perekonomiam Chairul Tanjung. Pemerintah dan pihak terkait sepakat untuk memulai
pembangunan bendungan raksasa atau proyek GSW tahap pertama sepanjang 33
kilometer yang diharapkan selesai dalam tiga tahun, yaitu pada 2017. Disamping itu
pembangunan proyek ini juga menelan Rp 500 triliun hingga 2030. Rencanannya dari
keseluruhan proyek sepanjang 33 kilometer tersebut, 8 (delapan) kilometer akan
dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, sedangkan sisanya dibangun oleh swasta.
Paparan diatas adalah gambaran bahwa proyek pembangunan tanggul raksasa
memiliki dampak yang melanggar prinsip etika lingkungan dalam pembangunan yang
menyebutkan bahwa dalam pembangunan tidak hanya hanya persoalan fisik dan
keuntungan ekonomi semata, tetapi juga perlu diperhatikan permasalahan sosial budaya.
Dampak yang melanggar etika lingkungan adalah :
Kerusakan ekosistem dimana pembangunan GSW ini akan banyak menghilangkan hutan
bakau (mangrove) yang ada di sepanjang pesisir teluk Jakarta. Mangrove adalah ‘rumah’
bagi berbagai macam ekosistem pesisir. Selain itu padang lamun dan terumbu karang
juga akan rusak juga.
Kerusakan di bidang sosial juga akan dialami oleh masyarakat pesisir. Dampak sosial
tersebut dapat dialami oleh ribuan masyarakat pesisir yaitu kehilangan pekerjaan,
kehilangan budaya dan kehilangan ruang terbuka hijau karena reklamasi. Reklamasi atau
GSW menyebabkan peninggian muka air laut. Dengan alat yang tidak memadai, akan
sulit bagi nelayan untuk bekerja seperti biasa. Jika proyek ini dilaksanakan sedikitnya
16.855 nelayan akan kembali lagi digusur dari ruang hidup dan ruang usahanya.
Dari sisi etika dan pembangunan, pembangunan Giant Sea Wall ini juga
melanggar etika pembangunan karena GSW ini hanya memperhatikan pembangunan
ekonomi yaitu perbaikan standar kehidupan khususnya standar material. Tujuan awal dari
proyek NCICD ini adalah menanggulangi banjir Jakarta, namun setelah melakukan
pengkajian, proyek NCICD ini diperkirakan akan menimbulkan dampak material yang
begitu besar berupa : (1) biaya kerugian yang dialami oleh banyak masyarakat terutama
nelayan atas kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian karena pemerintah harus
memberikan ganti rugi akan kehilangan tempat tinggal (2) biaya rehabilitasi lingkungan
yang timbul setelah proyek ini berjalan sangat besar contohnya biaya kerusakan
ekosistem pesisir (3) biaya pembangunan infrastruktur pendukung sangat besar dimana
pengembangan tanggul dan danau retensi akan mengharuskan relokasi semua
infrastruktur karena ; temperatur dalam danau akan menjadi terlalu panas untuk
berfungsinya pembangkit listrik secara efisien dan infrastruktur komunikasi dan energi
akan tertimbun dan rusak akibat dibangunnya tanggul dan reklamasi. Pada akhirnya
pembangunan NCICD ini merugikan banyak kualitas kehidupan dan disinyalir hanya
menguntungkan beberapa pihak swasta adalah investor dan developer proyek karena hasil
dari proyek NCICD ini berupa bangunan-bangunan mewah yang akan digunakan oleh
kaum elite saja.
Permasalahan ini juga tidak terceminkannya penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance) dalam rencana pembangunan GSW ini. Merujuk pada
prinsip etika penyelenggaraan pemerintah yang baik penyelenggaraan pemerintahan
harus benar-benar menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Hal ini terlihat
telah dilaksanakannya proses ground breaking proyek pada bulan Oktober 2014 lalu,
padahal proses pengkajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari Kementerian
Lingkungan Hidup belum diterbitkan. Dikemukakan oleh Asisten Deputi Bidang
Pengaduan dan Pelaksana Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
memastikan bahwa Proyek Tanggul Laut Raksasa belum memiliki izin Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. Izin AMDAL juga belum dimiliki dari Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bagi para pengembang Giant Sea Wall proyek NCICD ini. Hal ini juga
melanggar Pasal 111 UU Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa
pejabat harus menerbitkan izin lingkungan hidup sebelum proyek dikerjakan. Jika tidak,
maka akan terdapat konsekuensi pidana.
Selain itu, hal ini juga melanggar prinsip-prinsip etika penyelenggaraan
pemerintah yang lain yaitu: tidak dipenuhinya beberapa persyaratan teknis berupa
AMDAL dan KLHS, memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat memposisikan diri
sebagai pengawas bagi pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan proyek GSW karena
segala persyaratan dokumen kajian teknis ini sudah ada di peraturan perundang-undangan
yang disusun sendiri oleh pemerintah. Pemerintah sebagai subjek pembangunan telah
berhasil menyusun berbagai tools dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik
namun gagal sebagai pengawas karena tidak mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan
lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai pengawas, pemerintah harus mempunyai komitmen
moral sehingga memungkinkan mereka menjalani peran secara profesional.
Dalam UU LH No. 32 Tahun 2009 Pasal 22 menyatakan bahwa setiap usaha yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Giant Sea Wall
dalam proyek NCICD ini wajib menyertakan AMDAL karena :
Mengubah bentuk lahan atau bentang alam karena adanya reklamasi lahan dengan
menutup tanggul laut luar. Sehingga yang awalnya merupakan laut, akan diciptakan
menjadi daratan baru seluas 1.250ha untuk infrastruktur dan pengembangan perkotaan.
Reklamasi lahan pada sisi dalam tanggul laut akan memiliki ketinggian muka tanah
±3.77mLWS-2012
Mengeksploitasi SDA baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
Proses dan kegiatan Giant Sea Wall ini secara potensial menimbulkan pencemaran /
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan SDA dan
pemanfaatannya. Kerusakan yang akan disebabkan oleh Giant Sea Wall ini adalah
kerusakan lingkungan laut, dimana spesies laut yang menetap, jenis ikan dan benthos
akan musnah, kerusakan hutang mangrove dan padang lamun dan terumbu karang dan
akan menyebabkan bencana ekologis yang besar.
Proses dan kegiatan Giant Sea Wall dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan
buatan serta lingkungan sosial budaya.; Ada beberapa yang hilang akibat Giant Sea Wall
yaitu hilangnya Ruang Terbuka Hijau, hilangnya mata pencaharian para nelayan akibat
penutupan dari 2(dua) pelabuhan, dan kehilangan budaya di sekitar pesisir oleh para
nelayan.
Kegiatan ini memilik resiko yang tinggi dan mempengaruhi pertahanan laut dan
pengembangan kota ke arah laut. Giant Sea Wall ini dirancang karena pemerintah
menganggap bahwa Pertahanan Laut saat ini sudah tidak memadai karena memiliki
resiko yang tinggi akibat penurunan muka tanah, sehingga pemerintah merancang proyek
Giant Sea Wall ini.
Penerapan teknologi Proyek Giant Sea Wall ini akan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang membuat KLHS proyek
Giant Sea Wall dalam proyek NCICD. KLHS ini diperkirakan selesai pada tahun 2015.
Seyogianya, KLHS harus dibuat terlebih dahulu sebagai acuan dasar dalam rencana
pembuatan dokumen amdal. KLHS diharapkan tidak hanya mencakup isu sanitasi dan
kualitas air saja, namun juga harus mencakup perkiraan dampak dan resiko lingkungan ,
termasuk kinerja layanan / jasa ekosistem dan tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dalam proyek National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD) ini melanggar beberapa prinsip etika yaitu (1) etika
lingkungan dimana proyek ini tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan
hidup sehingga disinyalir akan menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan yang
mencakup kerusakan ekosistem serta kerusakan sosial, (2) etika pembangunan; proyek ini
tidak mencerminkan tujuan dari etika pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat tetapi akan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya
masyarakat pesisir dan hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tidak
memperhatikan aspek sosial budaya, (3) etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance); hal ini tercermin dari tidak dipenuhinya persyaratan teknis
administratif pelaksanaan pembangunan yang berupa dokumen AMDAL dan KLHS.
Kedua dokumen tersebut penting karena sudah tercantum dalam peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya tidak
dipenuhi.
Dilihat dari sejumlah prinsip etika yang dilanggar, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa belum adanya komitmen moral pemerintah dalam rencana
pembangunan GSW proyek NCICD ini. Komitmen moral ini berupa penerapan etika
secara konkret, bahwa etika tidak hanya membutuhkan pemahaman sebagai acuan untuk
melakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tetapi juga membutuhkan komitmen
dalam penerapannya, karena etika bukan merupakan peraturan yang tertulis tetapi
merupakan prinsip dasar yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil
oleh pemerintah.
B. Saran
Prinsip etika sangat penting dalam proses pembangunan. Pembangunan itu sendiri
terdiri dari 3(tiga) tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Sudah seharusnya prinsip etika menjadi salah satu hal yang penting yang harus dijadikan
dasar dalam setiap tahapan pembangunan demi tercapainya tujuan pembangunan yang
bertanggung jawab terhadap alam dan manusia serta memenuhi keadilan sosial. Khusus
dalam penerapannya, pada tahap perencanaan suatu kebijakan sangat diperlukan
pemahaman yang mendalam terhadap aspek sosial khususnya pemahaman terhadap
masyarakat. Aspirasi, kebutuhan dan permasalahan dalam masyarakat ini harus dipenuhi
oleh pemerintah, masyarakat disini harus meliputi semua kalangan karena apapun
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masyarakatlah yang akan merasakan dampak
langsung akibat kebijakan tersebut. Disamping aspek sosial, aspek lingkungan
merupakan bagian yang penting juga diperhatikan karena hubungan antara manusia dan
lingkungan tidak dapat dipisahkan sehingga dalam pembangunan manusia harus
bertanggung jawab terhadap lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA
Keraf, A.Sonny.2010.Etika Lingkungan Hidup.Kompas.Jakarta
Saturi, Sapariah,2014. Giant Sea Wall, Berikut Dampak Bagi Lingkungan dan
Nelayan.www.mongabay.com, diakses 14 Desember 2014
Winarno,Budi.2013.Etika Pembangunan.CAPS.Yogyakarta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009.Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,2014.Master
Plan.Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).Jakarta
______________,2014.Tanggul Laut Beresiko.www.kompas.com, diakses 14 Desember 2014
______________,2014.Tanggul Laut Wajib Memiliki AMDAL.
www.sinarharapan.co.news,diakses 9 Desember 2014