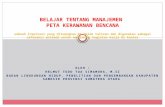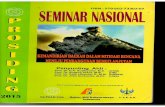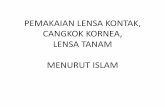Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Strategi Masyarakat dalam Mengatasi Dampak dan Upaya Menurunkan...
Transcript of Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Strategi Masyarakat dalam Mengatasi Dampak dan Upaya Menurunkan...
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 1
Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Strategi Masyarakat dalam
Mengatasi Dampak dan Upaya Menurunkan Tingkat Risiko Bencana:
Studi Kasus: Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Oleh: Lany Verayanti
Program Magister Sosiologi
Pascasarjana Universitas Andalas Padang
RINGKASAN
Pasca kejadian gempa bumi 30 September 2009, banyak lembaga bantuan
kemanusiaan yang datang ke wilayah terdampak termasuk di antaranya Nagari Batu
Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Di samping menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk logistik dan perlengkapan
darurat lainnya secara langsung, banyak juga di antara Organisasi Non Pemerintah
(ORNOP) ini berupaya melakukan program atau proyek Pengurangan Risiko Bencana
dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Namun pada praktiknya, tidak semua
lembaga ini secara murni melakukan penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dengan penggunakan prinsip partisipatif
seperti pendekatan berbasis komunitas yang ideal. Tidak hanya itu, seringkali bantuan
yang diberikan justru menjadi salah satu faktor yang menurunkan rasa solidaritas dan
modal sosial yang selama masa-masa darurat sebelum bantuan dari pihak luar datang terasa
semakin kuat di antara warga masyarakat yang menjadi korban.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dan cara-cara modal
sosial digunakan oleh warga masyarakat, peran bantuan dari pihak luar terkait dengan
modal sosial dan mendeskripsikan hubungan antara cara masyarakat mengatasi dampak
bencana dengan struktur sosial masyarakat wilayah penelitian. Dalam penelitian ini
digunakan metode kualitatif dengan konsep modal sosial Putnam dan teori masyarakat
aktif Etzioni yang dipakai sebagai sentral analisis yang akan dirujuk pada pembahasan
beberapa kasus yang ditemui pasca kejadian bencana gempa bumi 30 September 2009
yang menimpa Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
paradigma alternatif (paradigma teori kritis) dan pendekatan studi kasus.
Dalam penelitian ini digunakan konsep modal sosial yang dijabarkan oleh Putnam
mengacu pada fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan, yang
memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk saling menguntungkan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa modal sosial tidak saja berdampak positif dalam pengertian
memperkuat diri (self reinforcing) namun juga dapat berdampak negatif jika elemen
jaringan, norma dan kepercayaan yang menjadi prasyarat agar dapat saling memperkuat
diri tidak terpenuhi. Berbagai aksi kolektif yang dilakukan warga dalam mengatasi dampak
bencana gempa bumi di mana mereka menjadi korban terbukti dapat menjadi kekuatan
bersama dan pembangkit dari keterpurukan. Aksi kolektif yang dipandu oleh pemimpin
dengan pengetahuan yang dilandasi dengan kesadaran akan kondisi lingkunganya dan ditunjang oleh kemampuan dalam membentuk konsensus untuk mencapai kesepakatan-
kesepakatan di antara anggota kelompok menjadi faktor penting bagi munculnya
masyarakat aktif. Selain faktor kepemimpinan, faktor kesadaran dan pengetahuan akan diri
dan lingkungannya, peran individu dalam institusi sosial seperti kesehatan dan agama juga
berperan dalam mendorong warga korban bencana menjadi masyarakat aktif yang dapat
menentukan sendiri nasib mereka dan mengubah hukum sosial jika diperlukan.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 2
Namun begitu ketika modal sosial warga yang berfungsi untuk saling memperkuat diri
bersentuhan dengan kepentingan lain atau pihak luar (eksternal), ternyata justru berakibat
pada melemahnya modal sosial.
Kata Kunci: Gempa bumi, Modal Sosial, Jaringan, Norma, Kepercayaan.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 3
Penggunaan Jaringan, Norma dan Rasa Saling Percaya (Trust) dalam Mengatasi
Dampak Bencana
Seburuk apapun, dampak bencana harusnya bisa diatasi oleh warga karena
sebetulnya korban tidaklah pasif, hanya duduk meratapi nasib dan menunggu bantuan
datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka mampu mencari jalan keluar dari segala
kesulitan baik perseorangan maupun kolektif dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan
mereka melalui berbagai macam cara. Begitu pula dalam keadaan setelah bencana gempa
bumi 30 September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman, di mana jumlah korban baik
jiwa, harta maupun psikologis tidaklah sedikit.
Seperti dikatakan Putnam bahwa ide yang menjadi inti teori modal sosial adalah
jaringan sosial (Putnam, 2002: 6). Stok modal sosial ini mengarah pada memperkuat diri
(self reinforcing) dan bersifat kumulatif (Putnam, 1993: 4). Modal sosial mengikat,
menyatukan orang-orang yang memiliki kesamaan dalam hal-hal penting untuk
menghadapi masalah dan mencari jalan keluar bersama salah satunya adalah kesamaan
wilayah tempat tinggal.
Warga Batu Kalang hidup berkelompok baik dalam satu kesatuan genealogis
tertentu seperti suku maupun dalam satu kelompok kecil yang terdiri dari dua atau lebih
suku atau beberapa buah rumah yang berdekatan dan saling terhubung dalam ikatan sosial
budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini menampakkan perannya yang besar
dalam mengatasi dampak bencana dengan saling membantu untuk memperkecil tingkat
risiko bencana yang lebih besar yang mungkin akan didapat jika persoalan di depan mata
tidak dihadapi atau ditanggulangi bersama. Seperti yang akan disajikan berikut ini, warga
menggunakan jaringan sosial, norma serta mengandalkan rasa percaya mereka terhadap
orang-orang tertentu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sebagai dampak dari
bencana.
Sepanjang sore hingga malam hari setelah gempa besar itu, masih terjadi beberapa
kali gempa susulan dengan kekuatan dan intensitas guncangan yang makin lama makin
menurun. Namun begitu, ketakutan dan kepanikan mereka hadapi bersama dengan
berkumpul dalam suatu tempat tertentu dan berusaha saling melindungi dan saling
menenangkan. Mereka berkumpul di rumah tetangga yang masih bisa ditempati, di dalam
tenda-tenda darurat yang mereka buat dari terpal plastik yang biasanya digunakan untuk
menjadi alas atau penutup komoditas pertanian yang dijemur setelah dipanen atau di laga-
laga, surau atau rumah sanak keluarga yang masih layak ditempati. Berapapun jumlah atau
apapun yang dimasak akan dinikmati bersama-sama.
Sejak hari ke 2 pasca kejadian gempa bumi warga saling membantu membangun
hunian sementara di depan atau samping rumah warga. Kegiatan ini dilakukan oleh
sekelompok warga yang tinggal berdekatan atau mengelompok dengan sistem julo-julo
karajo atau julo-julo tanago. Sistem julo-julo ini hampir sama dengan arisan yang
pelaksanaannya bergiliran dari satu rumah anggota ke rumah lainnya di waktu yang
berlainan, namun pada julo-julo ini, yang diterima pemilik rumah bukanlah uang akan
tetapi tenaga dari anggota lainnya. Satu hunian sementara untuk satu keluarga biasanya
bisa mereka selesaikan bersama-sama dalam waktu satu hari. Bangunan ini pada umumnya
didirikan berbentuk bangunan kamar dari seng atau triplek dari sisa bangunan yang masih
bisa dipakai beratapkan terpal plastik atau hanya berupa tenda-tenda dari terpal plastik jika
tidak ada sisa bahan bangunan yang bisa digunakan lagi.
Selama tiga hari pertama warga bertahan dengan memanfaatkan bahan-bahan
makanan sendiri. Mereka menggunakan cadangan beras di bawah tumpukan puing-puing
rumah-rumah mereka yang hancur atau rusak berat, dari Hueller (Rice Milling) atau yang
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 4
lebih akrab dengan sebutan heler. Sementara untuk lauk pauk mereka hanya
mengkonsumsi sayur yang ada di sekitar rumah, mie instant atau telur dari beberapa
warung yang tersisa atau masakan hari raya yang masih bisa dikonsumsi.
Hal lain yang menggambarkan secara nyata bekerjanya norma sosial yang menjadi
dasar jaringan sosial dan turut memperkuat modal sosial di Nagari Batu Kalang pasca
gempa bumi 30 September 2009 adalah perbuatan saling tolong menolong, bahu membahu
keluar dari kesulitan di antara para korban bencana itu sendiri. Meskipun mereka semua
adalah korban bencana, menolong korban yang tertimpa reruntuhan meskipun rumah
mereka juga roboh, adalah sebuah keharusan. Menyelenggarakan mayat meskipun mereka
juga dalam keadaaan duka yang mendalam karena menjadi korban adalah kewajiban
sesama muslim dan urang kampuang (orang kampung); mengajak keluarga lain yang tidak
memiliki persediaan untuk menikmati bersama hasil olahan makanan keluarga yang masih
menyimpan persediaan beras, lauk-pauk yang cukup; menyumbangkan beras kepada sanak
keluarga dan orang kampung; memberi tumpangan kepada sanak keluarga dan/atau
tetangganya yang rumahnya tidak lagi bisa ditempati oleh keluarga yang rumahnya masih
bisa ditempati, dan lain sebagainya.
Kuatnya jaringan sosial di antara warga diperkuat oleh norma-norma yang ada dan
hidup di dalam adat dan budaya warga masyarakat setempat. Semua hal ini sesuai dengan
adat hidup orang Minangkabau yakni:
Adat hiduik tolong-manolong : Adat hidup tolong-menolong
Adat mati janguak-manjanguak : Adat mati saling melayat
Adat lai bari-mambari : Adat kaya beri-memberi
Adat tidak baselang tenggang : Adat miskin saling membantu
Adat hiduik tolong-manolong mengisyaratkan bahwa orang Minang tidak boleh
menganut paham individualistis yang hanya memikirkan diri sendiri, atau hanya mengurus
kepentingan sindiri sertapeduli pada lingkungan. Yang lemah dan kesulitan harus dibantu,
tetangga harus diperhatikan. Hidup dan kehidupan kekerabatan dan kekeluargaan lebih
diutamakan dibandingkan dengan kedirian. Adat mati janguak-manjanguak menunjukkan
bahwa kesedihan tetangga merupakan kesedihan kita juga. Sebagai tetangga, kenalan,
karib kerabat, apalagi dunsanak, adalah kewajiban kita untuk meringankan beban batin
keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan adat lai bari-mambari, Adat tidak baselang
tenggang bermakna mereka yang mendapat rezeki cukup berkewajiban untuk memberi
bantuan kepada yang membutuhkan. Begitulah pula mereka yang dalam kesulitan ekonomi
wajar sekali untuk mencari bantuan (M.S, 2011: 82-83).
Struktur Sosial Sebagai Tambatan Modal Sosial Modal sosial tertambat pada struktur sosial. Modal sosial terdiri dari beberapa
aspek struktur sosial dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor - baik individu
maupun kelompok dalam struktur. Karena itu, struktur sosial turut memfasilitasi
terbentuknya modal sosial. Sebaliknya, struktur sosial itu tidak dengan sendirinya menjadi
tambatan modal sosial kalau tidak ada individu atau kelompok yang memanfaatkan atau
memfungsikan struktur sosial itu untuk keperluan individu atau kelompok.
Struktur sosial di sini bisa berada pada tataran mikro seperti status dan peran
beserta nilai dan norma yang melandasi hubungan di antara aktor; pada tataran mezo dalam
institusi sosial maupun makro dalam stratifikasi sosial (Lawang, 2005). Dari kasus-kasus
yang dibahas dalam penelitian ini, nampak bahwa keluarga (keluarga inti maupun keluarga
luas) dan tetangga, institusi sosial maupun pemimpin (formal dan informal) memainkan
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 5
peranan yang sangat penting dalam mengatasi dampak bencana. Hubungan di anatar para
aktor yang terdapat pada ketiga tataran struktur sosial.
Dalam kajian merantau, Naim (2013: 65) menggambarkan bahwa wilayah budaya
minangkabau berpusat di Luhak nan Tigo yang terdiri dari Luhak Tanah Datar, Agam dan
50 Kota. Dari ketiga luhak ini kemudian berekspansi ke dataran rendah pantai barat (rantau
pesisir) maupun ke timur (rantau timur). Selain luhak, ketiga wilayah asal minangkabau ini
juga dikenal sengan sebutan darek. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman adalah salah
satu wilayah rantau. Wilayah Pariaman yang terletak di rantau pesisir yang di samping
berfungsi sebagai pusat perdagangan, rantau pesisir juga berfungsi sebagai pusat-pusat
kegiatan dakwah Islam (Naim, 2013: 76). Berbeda dengan masyarakat darek yang
homogen, masyarakat Padang Pariaman adalah masyarakat heterogen. Karena persentuhan
masyarakat pantai secara terus menerus dengan para pendatang asing menyebabkan
mereka memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat darek. Mereka lebih bersifat
inklusif terhadap perbedaan yang datang silih berganti (Suryadi, dalam Natsir 2011: 54).
Beberapa bentuk dari sistem matrilinial yang berlaku di darek juga tidak dipatuhi di rantau
ini seperti pemberian gelar Sidi, Bagindo atau Sutan yang merupakan gelar turunan dari
Bapak, tradisi „jemputan‟. topografi yang tidak sesubur di daratan yang membuat
masyarakatnya banyak menjadi pedagang yang cendrung materialistik membentuk watak
penduduknya (Ka‟bati, 2009).
Makna dari kata sosial dalam modal sosial haruslah bersifat positif. Dia harus
mampu mejadi alat perekat di antara warga masyarakat atau anggota sebuah kelompok
untuk dapat menghasilkan solusi yang baik dari pemecahan masalah sosial yang dihadapi.
Karena itu, peran dan status seseorang beserta nilai dan norma yang terkandung di dalam
dalam hubungan-hubungan sosial di antara individu dalam masyarakat atau dengan kata
lain hubungan-hubungan yang terjadi di dalam memenuhi status dan peran sangatlah
penting dilihat dalam proses membangun kerekatan ini. Status seseorang sebagai orangtua,
suami, istri, anak, pastilah memiliki peran tertentu dalam sebuah rumah tangga yang diikat
oleh nilai dan norma dalam masyarakat, begitu pula halnya dengan status sebagai tetangga
atau teman. Dalam mempertahankan sebuah hubungan, tiap individu senantiasa berusaha
melakukan hal-hal yang baik, yang dapat menguntungkan dirinya dan orang lain sesuai
dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Hubungan ini terus dipertahankan agar suatu
saat nanti ketika dia berada dalam sebuah kesulitan, orang lain yang diharapkannya dapat
membantu keluar dari kesulitan memang betul-betul dapat berperan sesuai dengan
harapannya itu.
Di dalam satu kelompok rumah warga di Minangkabau yang biasa disebut sebagai
kampuang ketek biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan atau
hubungan perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari warga saling berinteraksi dan
berusaha membangun hubungan baik yang saling menguntungkan di antara mereka.
Kejadian bencana gempa bumi yang telah menyebabkan kehilangan dan kerugian telah
mendorong warga untuk bekerja bahu membahu keluar dari kesulitan yang mereka hadapi.
Keluarga dalam masyarakat minangkabau dapat juga berarti keluarga inti dan keluarga
luas. Dalam penanganan korban bencana, mengatasi kesulitan bahan makanan, pakaian,
pengobatan, pembangunan hunian baik sementara maupun permanen menjadi
tanggungjawab dan dilakukan bersama antara orangtua, anak, suami, istri, cucu, nenek,
kakek, mamak, mamak rumah, mamak kapalo warih, anak pisang, bako, dan lain
sebagainya.
Apa yang dilakukan warga korban bencana untuk saling melindungi dan saling
menguatkan serta saling bantu dalam menghadapi kesulitan bersama ini tentu saja tidak
terjadi secara tiba-tiba. Hubungan atau kedekatan (jaringan sosial-pen) yang selama ini
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 6
terbangun di antara individu dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu membuat
mereka yakin dapat saling mengandalkan dalam memecahkan persoalan bersama. Interaksi
di antara anggota kelompok atau komunitas memungkinkan untuk saling mengenal satu
sama lain dan karena itulah rasa saling percaya di antara mereka tumbuh. Hubungan dan
rasa saling percaya ini diikat oleh norma bersama yang sangat mereka yakini bahwa setiap
kesulitan, jika dihadapi bersama tidak saja akan meringankan beban orang yang ditolong,
namun juga akan dapat menolong kita di masa depan. Terlebih lagi, mereka semua adalah
korban gempa bumi yang sama-sama menderita. Penderitaan jika dihadapi bersama akan
semakin terasa ringan.
Dalam masyarakat yang komunal seperti masyarakat Minangkabau, semua tugas
menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong menjadi keharusan, saling membantu
dan menunjang menjadi kewajiban. Yang berat sama dipikul dan yang ringan sama
dijinjing (Amir, M.S, 2011: 122). Ini tergambar dalam pepatah Minangkabau yang
berbunyi:
Nan barek samo dipikua : Yang berat sama dipikul
Nan ringan samo dijinjiang : Yang ringan sama dijinjing
Ka bukik samo mandaki : Ke bukit sama mendaki
Ka lurah samo manurun : Ke lurah sama menurun
Nan ado samo dimakan : Yang ada sama dimakan
Nan indak samo dicari : Yang tidak sama dicari
Di sisi lain, norma juga memegang peranan yang sangat signifikan dalam
memperkuat jaringan sosial warga. Norma berisi suatu keharusan bagi individu atau warga
masyarakat dalam berperilaku, menjadi pedoman bagi individu apa yang harus dilakukan,
bersikap dan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada serta memiliki pengaruh yang
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, norma sering
disebut sebagai adat, seperti yang dinyatakan oleh Amir. M.S (2011: 189) bahwa adat
adalah aturan hidup berkelompok (bermasyarakat) yang ditaati secara turun temurun dari
masa ke masa.
Pepatah Nan buruak dibuang jo etongan, nan elok dipakai jo mufakat (Yang buruk
dibuang dengan perhitungan, yang baik dipakai dengan mufakat) memperlihatkan kepada
kita bahwa adat Minang mempunyai daya lentur yang luar biasa (Amir, M.S, 2011: 73) dan
ini terlihat pada kasus Baharuddin. Kelenturan ini telah memperkuat rasa saling percaya
semakin meningkatkan hubungan kekerabatan dan sosial serta rasa persaudaraan di antara
para korban bencana yang saling memperkuat diri (self reinforcing).
Norma yang ada dalam masyarakat dengan tingkat ikatan dan keeratan hubungan
antara satu individu dengan individu yang lain cukup kuat seperti pada wilayah penelitian
ini menjadi jaringan kontrol yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan atau mengatasi
masalah bersama. Untuk mengontrol perilaku dalam hubungan di antara warga, seseorang
haruslah memiliki pengetahuan dan komitmen untuk mencapai sebuah tujuan bersama agar
mereka dapat memutuskan tindakan apa yang tepat diambil dalam mengatasi dampak
bencana. Tanpa komitmen bersama yang diwujudkan dalam tindakan, tidak akan terjadi
apa yang disebut Etzioni sebagai masyarakat aktif. Tanpa komitmen, warga hanya akan menjadi orang-orang yang pasif dan pasrah.
Kejadian bencana telah terbukti memperkuat jaringan sosial di antara warga di tiap
kampung maupun secara keseluruhan di dalam nagari dengan ditunjang oleh norma yang
terbangun dalam masyarakat. Di antara orang-orang yang memiliki kesamaan baik nasib,
kepentingan maupun genealogis serta di antara warga yang tinggal berdekatan telah
menjadi dasar bagi munculnya rasa solidaritas dan kesetiakawanan di antara mereka. Tipe
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 7
hubungan masyarakat yang seperti ini disebut Tӧnnies sebagai hubungan darah
(relationship by blood) dan hubungan pertetanggaan (relationship by neighbourliness)
dalam konsep gemeinschaft yang dia kemukakan.
Korban yang sadar betul akan keterbatasan kemampuan diri dan keluarganya
dalam menghadapi dampak bencana mengambil keputusan untuk saling bantu dalam
keadaan yang serba sulit. Diminta atau tidak, memiliki hubungan kekerabatan atau tidak,
orang-orang yang tinggal dalam satu lingkungan teritorial tertentu bertindak meringankan
beban orang atau keluarga yang dianggap paling tinggi memiliki kesulitan.
Kesadaran akan diri dan lingkungannya ditunjang oleh pengambilan keputusan
yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang dilandasi oleh nilai dan norma serta tujuan
hidup bersama telah menjadikan warga korban bencana di Nagari Batu Kalang menjadi
masyarakat yang aktif. Mereka mengambil tindakan-tindakan berdasarkan komitmen
personal maupun kelompok agar dapat megontrol sendiri nasib diri sendiri. Adat babuhue
sentak telah menjadi dasar bagi keputusan dan tindakan yang diambil oleh keluarga
korban dan anggota sukunya yang lain sehingga penerapan norma adat tidak lagi terlalu
ketat dan dapat menanggulangi kebutuhan korban bencana.
Unit sosial seperti organisasi yang ada di dalam masyarakat ditujukan salah satunya
untuk mengatasi masalah sosial. Seperti sudah disinggung sebelumnya, bahwa bencana
juga dipandang sebagai salah satu masalah sosial yang menyebabkan terganggunya unit-
unit sosial di dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya itulah, organisasi
sosial yang ada dalam masyarakat diharapkan mampu mengatasi dampak dari kejadian
bencana seperti memberikan pelayanan dan perlindungan kepada keluarga korban atau
jaminan sosial tertentu sehingga mereka dapat terus melanjutkan hidupnya.
Namun kenyataan yang nampak di berbagai kejadian bencana, unit-unit atau
organisasi sosial banyak yang tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Ketika unit-
unit sosial tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi anggota kelompok atau
warganya, maka ancaman atau bahaya sekecil apapun dapat berubah menjadi bencana.
Karena itu, berbagai upaya harus dilakukan secara bersama-sama dalam menyadari dan
memahami ancaman atau bahaya yang dihadapi sehari-hari serta menemukan cara atau
alternatif pemecahan masalah untuk menanggulanginya. Pengetahuan dan kesadaran satu
orang, satu keluarga harus terus diperluas kepada seluruh warga agar menjadi kesadaran
bersama sehingga dapat menimbulkan aksi-aksi nyata yang dapat melindungi mereka
semua dari ancaman atau bahaya.
Pengalaman seorang ketua UEMSP dapat menjadi pembelajaran penting bagi kita.
Sebagai pemimpin dengan cara berpikir berbeda dari kebanyakan orang dengan melihat
bahwa korban juga adalah orang-orang yang berdaya dan mampu segera bangkit dari
kesulitan ditunjang oleh kemampuannya persuasifnya mampu mempengaruhi keputusan
anggota kelompok. Pandangannya terhadap keberdayaan korban bencana dan situasi serta
kondisi riil telah membantunya dalam menemukan solusi untuk membantu anggota
kelompok keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dalam masa kepemimpinannya yang selalu
mengutamakan hubungan baik dan komunikasi dengan anggota yang diikat oleh
kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama telah membuahkan tingkat kepercayaan
di antara mereka yang cukup tinggi dan dengan demikian telah mampu meningkatkan
modal sosial di antara anggota kelompok.
Pada kasus lainnya, meskipun tidak memiliki status sebagai pemimpin sebuah
kelompok atau organisasi tertentu, ketokohannya selama ini sangat diakui oleh warga
Nagari Batu Kalang. Dia adalah seorang perempuan yang pernah menjadi kepala desa pada
era orde baru dan merupakan tokoh yang selalu dijadikan panutan dan tempat warga
berkeluh kesah. Kelincahannya dan kemampuan membangun hubungan dengan warga
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 8
lainnya maupun dengan kelompok atau warga lain di luar nagari sangat membantunya
dalam proses interaksi sehari-hari dengan orang lain. Perannya sebagai tokoh atau
pemimpin informal kemudian nampak pada situasi darurat pasca bencana. Dengan
pengalamannya dalam mengorganisir masyarakat dan luasnya hubungan dengan pihak luar
ditunjang oleh sikap luwesnya dan pemikiran yang berorientasi pada pemecahan maslah
bersama, dia kemudian mengambil peran sebagai pengelola posko Korongnya. Tidak
hanya sekedar mengelola bantuan yang sampai di posko korong saja, dia juga mendorong
anak-anaknya untuk dapat mencari alternatif pemecahan masalah kebutuhan untuk
bertahan hidup dengan memanfaatkan posisi dan jejaring anak-anaknya dalam menggalang
bantuan dari para perantau.
Peran institusional dalam menghadapi dampak bencana turut mempertegas
kelekatan atau ketertambatan modal sosial dengan struktur sosial khususnya pada level
mezo. Kebutuhan krusial para korban baik terkait dengan kesehatan fisik maupun mental
jika tidak diintervensi oleh peran institusional seperti digambarkan di atas akan dapat
berdampak sangat buruk yang bisa saja berupa kematian atau depresi. Pengetahuan dan
keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang mewakili institusi ini, tanpa dibarengi
dengan komitmen individu dari petugas yang diwujudkan dalam tindakan konkrit tidak
akan menolong korban dan keluarganya untuk dapat bangkit dari keterpurukannya. Melalui
peran kedua institusi ini warga korban bencana menjadi masyarakat aktif yang dapat
menentukan sendiri nasib mereka serta lebih tenang dan bisa lebih fokus berpikir untuk
mencari alternatif pemecahan solusi dari masalah lainnya yang mereka hadapi, misalnya
masalah keterbatasan makanan, pakaian dan tempat berlindung.
Tipologi Modal Sosial dalam Menghadapi Dampak Bencana
Modal Sosial Menjembatani (Bridging) dan Modal Sosial Berwawasan ke luar (Out
Ward Looking)
Hal ini nampak mana kala cara dan orientasi berpikir seorang pemimpin kelompok
memandang bahwa semua orang dapat berperan dan memiliki hak dan kewajiban yang
sama dalam memecahkan masalah. Hal ini ditunjang oleh sikap hidup yang selalu
membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, terbukti dapat menyumbang pada
pemenuhan kebutuhan warga korban bencana. Seperti apa yang dikatakan Putnam bahwa:
“....sebuah komunitas yang hanya memiliki bonding social capital
saja dan tidak memiliki bridging social capital berada dalam
bahaya serius....”
Bahaya yang serius mungkin saja berupa kelaparan, penyakit dan kematian yang
merupakan dampak ikutan setelah sebuah kejadian bencana. Ini mungkin saja terjadi pada
kasus ini bila tidak ada orag-orang seperti mengambil peran dalam menjembatani
kebutuhan ini. Bantuan yang berdatangan dari rantau didistribusikannya kepada sanak
keluarga dan warga lainnya di Korong tersebut. Hasbullah (2006: 31) menyatakan:
“Orientasi kelompok dengan tipologi bridging social capital dalam
gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi “fight for”
(berjuang untuk) yang mengarahkan pada pencarian jawaban
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 9
bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
kelompok (pada situasi tertentu)..... “
Sementara, banyak kasus lainnya di mana anak-anak korban yang pulang dari rantau
masih banyak yang berpikir hanya untuk menyelamatkan keluarganya saja, tidak atau
belum berpikir untuk turut membantu warga lain di kampung halamannya terutama bagi
korban yang tidak memiliki sanak keluarga di rantau yang mampu atau berkesempatan
pulang ke kampung untuk membantu mereka.
Modal Sosial Formal dan Informal
Meskipun semua adalah korban, namun tanggungjawab sebagai peminjam untuk
mengembalikan dana pinjaman dan hak sebagai anggota untuk dapat mengakses pijaman
selalu berusaha dijamin keberlangsungannya oleh para pengurus. Mengingat kondisi pasca
bencana, pengurus dan anggota membangun kembali kesepakatan dari yang semula
pinjaman hanya diperbolehkan untuk usaha menjadi sedikit lebih longgar, untuk
mencukupi kebutuhan hidup dan membeli perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Dengan
berpegang pada tujuan dan kesepakatan bersama, salah satu kelompok UEMSP di Nagari
Batu Kalang ini telah terbukti mampu menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan anggota.
Modal sosial informal seperti kelompok julo-julo, pengajian, majelis taklim, posko
mandiri (meskipun didirikan sebagai bentuk kekecewaan) telah mampu menjadi jawaban
atas kesulitan yang dihadapi para korban. Kebutuhan untuk bersama-sama melakukan
sebuah upaya keluar dari kesulitan dengan prinsip saling menguntungkan dilakukan
kelompok julo-julo dalam membangun hunian sementara maupun permanen. Sementara
pemenuhan kebutuhan secara psikologis atau dalam bentuk ketenangan batin agar dapat
segera bangkit dari keterpurukan dipenuhi oleh kelompok pengajian dan majelis taklim.
Modal Sosial Mengikat (Bonding) dan Modal Sosial Berorientasi ke Dalam (Inward
Looking) ; Limitasi Modal Sosial
Tipologi modal sosial mengikat (bonding) ini biasanya bersifat eksklusif. Dia berada
di antara, dilakukan dan digunakan oleh serta bermanfaat bagi individu anggota sebuah
kelompok, organisasi atau komunitas tertentu. Mereka biasanya adalah orang-orang
dengan kesamaan tertentu seperi suku, ras, agama, kepentingan, kesamaan wilayah tempat
tinggal (teritorial) dan lain sebagainya. Karena itu, peran, hubungan, tanggungjawab dan
perhatian lebih berorientasi ke dalam dibandingkan ke luar.
Modal sosial dengan tipe seperti ini nampak sekali pada hubungan kekerabatan dan
pertetanggaan masih sangat kuat diikat oleh norma bersama-sama bahu membahu
mengatasi kesulitan yang dihadapi. Meski semua orang adalah korban, namun norma
“yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing” sudah sangat menginternalisasi dan
mewarnai kehidupan masyarakat. Apa yang masih bisa dilakukan dalam membantu
meringankan penderitaan orang lain harus dilakukan oleh orang-orang yang tinggal dalam
komunitas tersebut.
Namun meski pada ketiga kasus tersebut modal sosial warga korban bencana nampak
meningkat, tidak begitu halnya dengan kasus pendirian posko mandiri. Semangat
solidaritas dan kedekatan hubungan serta kesamaan wilayah tempat tinggal membuat
pengurus posko korong tidak dapat mengembangkan solidaritasnya kepada anggota
kelompok warga lainnya, meskipun masih berada dalam satu korong. Jalinan kohesivitas
kultural yang tercipta belum tentu merefleksikan kekuatan modal sosial dan dalam
kelompok masyarakat seperti ini hanya ada “kami” sebagai “kita” serta kebenaran
berperilaku dan etika ada pada kelompok kami (Hasbullah, 2006: 26).
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 10
Kondisi seperti inilah yang kemudian membuat modal sosial menjadi terbatas.
Kekuatan modal sosial hanya terbatas pada satu lingkungan atau kelompok kecil saja dan
pada keadaan tertentu dapat merugikan kelompok lain. Limitasi modal sosial pada kasus
pendirian posko mandiri, julo-julo menghilang, upah buruh melambung dan tukang gempa
serta kasus manipulasi data menunjukkan kepada kita bahwa modal sosial warga korban
bencana menjadi melemah ketika bersentuhan dengan bantuan (sumberdaya) eksternal
yang direncanakan dan dikelola dengan tidak mempertimbangkan sumberdaya internal
atau energi sosial yang dimiliki warga korban bencana.
Bagaimanapun, masyarakat memiliki cara-cara sendiri yang mereka bangun untuk
menghadapi kesulitan bersama secara internal berdasarkan nilai dan norma yang ada dan
mengikat hubungan di antara mereka. Kesadaran diri akan situasi lingkungan, kemampuan
diri dan diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk dapat saling
merigankan beban, saling bantu serta saling mengandalkan menjadikan warga korban
bencana menjadi masyarakat aktif yang mampu menentukan sendiri nasib mereka dan
dapat mengubah hukum sosial.
Itulah mengapa penting mempertimbangkan sumberdaya internal atau energi sosial
yang telah ada dan berkembang di antara korban bencana harus menjadi pertimbangan
penting bagi tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pihak eksternal yang akan
membantu mereka. Bukannya meringankan beban, interaksi bantuan dari pihak eksternal
dengan modal sosial warga korban bencana malah justru dapat menurunkan modal sosial
yang telah ada.
Di sisi lain, untuk dapat terus menjadi masyarakat aktif yang dapat menguasai dunia
sosial, mampu mengendalikan diri sendiri dan dapat mengubah hukum sosial, masyarakat
harus terus berupaya mengembangkan kesadaran diri terhadap kondisi lingkungan.
Kesadaran dan pengetahuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk
kebaikan diri, keluarga dan kelompok kecil di mana mereka hidup akan menjadi kunci dari
masyarakat aktif yang dapat membimbing dirinya sendiri (self guiding). Pemimpin dan
institusi yang ada dapat memainkan peranan penting dalam mendorong masyarakat untuk
bernegosiasi dalam mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak akan sangat
membantu untuk tetap menjadi masyarakat aktif.
Kesimpulan
Modal sosial yang digunakan terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan dan norma.
Dalam dimensi jaringan sosial, kelompok kekerabatan dan ketetanggaan (teritorial) paling
umum digunakan. Ini menunjukkan bahwa tipe hubungan gemeinschaft yang dikemukakan
Tӧnnies menjadi dasar modal sosial warga. Jaringan dari kelompok kekerabatan di sini
tidak hanya dari kekerabatan matrilineal, melainkan juga dengan kelompok kekerabatan
dari pihak bapak (laki-laki). Jaringan sosial ini bekerja dan berkontribusi berdasarkan
norma-norma adat dan agama tentang saling membantu, bukan berdasarkan pertukaran
sosial. Rasa percaya terhadap kerabat yang dapat diandalkan untuk menjadi jembatan
penghubung yang sangat penting terhadap aktor-aktor.
Warga korba bencana di Nagari Batu Kalang ditemukan menggunakan modal sosial
menjembatani (bridging social capital) dan modal sosial berwawasan ke luar (Out Ward
Looking). Orang-orang yang tidak memiliki kesamaan satu sama lain disatukan dalam
kepentingan untuk membantu korban bencana yang difasilitasi oleh seseorang dalam
komunitas yang menyadari betul pentingnya mencari dukungan akan pemenuhan
kebutuhan pasca bencana. Kesadaran bahwa semua orang dalam komunitas memiliki hak
yang sama untuk mendapatkan bantuan ini diwujudkan melalui aksi-aksi voluntarisme.
Modal sosial berwawasan ke luar ditunjang oleh jaringan eksternal yang luas dalam
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 11
kerangka mencapai tujuan pemecahan masalah yang diahadapi bersama terbukti menjadi
faktor yang penting dalam meningkatkan modal sosial.
Di samping itu, modal sosial formal dan informal juga ditemukan dalam wilayah
penelitian. Bentuk modal sosial ini berkembang dan meningkat ketika penggunaannya
ditunjang oleh faktor kepemimpinan yang memiliki hubungan atau jaringan sosial yang
kuat dengan anggota atau warga lainnya, memiliki integritas tinggi dan terbukti dapat
dipercaya sebagai orang yang dapat diandalkan dalam mencari jalan keluar dari kesulitan
bersama. Selain itu, dia juga haruslah orang yang memiliki kemampuan negosiasi untuk
mempengaruhi tindakan orang-orang yang berada di dekatnya agar sesuai dengan apa yang
diinginkannya. Inilah yang kemudian menjadi faktor penting bagi munculnya masyarakat
aktif.
Dalam penelitian ini juga ditemukan kenyataan bahwa modal sosial mengikat
(bonding) dengan modal sosial berwawasan ke dalam (inward looking) selain berguna
dalam mempererat kohesivitas dan rasa solidaritas kelompok juga sekaligus sebagai
penghambat berkembang atau meningkatnya modal sosial warga korban bencana.
Solidaritas dan kedekatan hubungan serta kesamaan wilayah tempat tinggal membuat
orang-orang yang berada dalam satu kelompok tidak dapat mengembangkan solidaritasnya
kepada anggota kelompok lainnya.
Limitasi ini berpengaruh pada keputusan seseorang untuk bekerjasama, rasa saling
percaya saling bantu dan saling mengandalkan untuk keluar dari kesulitan yang sama-sama
dihadapi. Akibatnya dalam kasus-kasus yang diungkapkan di dalam penelitian ini, modal
sosial warga menjadi menurun ketika bersentuhan dengan bantuan eksternal yang dikelola
dengan tidak mempertimbangkan sumberdaya internal (modal sosial) warga.
Dengan demikian kemampuan masyarakat aktif dalam menentukan sendiri nasib
mereka dapat terganggu ketika bersentuhan dengan sumberdaya eksternal yang sulit
dikontrol secara internal. Ketidakmampuan mengontrol di sini disebabkan oleh situasi dan
kondisi yang dihadapi saat banyaknya bantuan datang ditengah-tengah kekurangan dan
tingginya tingkat kebutuhan yang dirasakan warga korban bencana. Di sinilah letak
pentingnya bantuan dari pihak luar untuk dapat menjembatani (bridging) kebutuhan warga
korban bencana.
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa modal sosial bekerja di dalam dan
tertambat pada struktur sosial masyarakat baik dalam level mikro dan mezo. Pada level
mikro, posisi dan peran seseorang dalam sebuah komunitas yang memiliki tingkat
kohesivitas yang tinggi. Di sini hubungan yang terjalin diatur oleh norma dan dilandasi
rasa saling percaya dan telah terbukti menjadi faktor yang sangat kuat dalam mendorong
modal sosial. Institusi sosial (dalam kasus ini ditunjukkan oleh institusi kesehatan dan
agama) yang dalam hal ini diwakili oleh individu seperti bidan, garin, labai, memiliki
peranan yang sangat penting dalam menolong korban bencana. Sementara dalam tataran
makro, peran pemimpin formal dan informal dengan cara berpikir serta integritas yang
tidak dipertanyakan menjadi sangat signifikan. Ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi
dan negosiasi yang baik dalam menggalang dukungan dalam menentukan tindakan, tipe
pemimpin seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat bertindak dan menentukan
arah nasib mereka sendiri ke depannya.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa poin penting yang penulis anggap penting
untuk menjadi rekomendasi bagi para pihak adalah sebagai berikut:
1. Korban bencana bukanlah orang-orang yang sama sekali tanpa daya, pasif dan
pasrah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penguatan institusi, sistem atau struktur
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 12
sosial yang ada dalam masyarakat baik oleh pemerintah daerah setempat dan
terutama oleh warga masyarakat itu sendiri.
2. Untuk dapat menemukan sumber kekuatan sosial warga korban bencana Pemerintah,
dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu menyusun sebuah alat (tool)
penilaian pasca bencana yang di dalamnya selain mengidentifikasi dampak
kerusakan dan kerugian secara fisik, ekonomi dan psikologis, juga daftar kebutuhan
bagi kelompok khusus serta upaya-upaya yang telah dilakukan warga dalam
mengatasi dampak bencana sehingga bantuan yang diberikan kepada korban dapat
lebih optimal.
3. Mengingat besarnya tingkat bahaya atau ancaman serta risiko bencana di wilayah
Sumatera Barat, perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis dalam
meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta kemampuan teknis
masyarakat untuk meminimalkan risiko dan mengelola dampak bencana.
Sistematisasi di sini termasuk jaminan keberlanjutannya dengan memasukkannya
dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah.
4. Pendekatan cash for work dalam mengatasi persoalan atau dampak bencana harus
diganti dengan yang lebih memberdayakan warga korban dan meminimalkan tingkat
kecurangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, menemukan dan mengenali dengan
tepat apa yang menjadi kebutuhan dan sumberdaya lokal termasuk sistem dan
struktur sosial yang ada menjadi sangat penting sehingga dapat ditemukan strategi
yang tepat pula. Dalam hal ini peneliti mengusulkan kalau dalam profil nagari juga
disertakan gambaran dan analisa mengenai hubungan antara bahaya atau ancaman
serta risiko bencana – dalam hal ini tidak hanya alam - yang ada di wilayah itu
dengan sumberdaya lokal yang ada dan memungkinkan untuk menjadi sarana untuk
mengurangi risiko atau mengelola dampak bencana.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adnan, Nurlela, 2001, Kamus Bahasa Indonesia-Minangkabau, Balai Pustaka, Jakarta,
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Adolf, Frank, The Interaction of Collective Actors, dalam McWilliams, Wilson Carey, The
Active Society Revisited, 2006, Wilson Rowman & Littlefield publishers, Inc,
USA.
Afrizal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Dari Pengertian Sampai Penulisan
Laporan, Laboratorium Sosioligi FISIP Unand, Padang.
Affeltrnger et al., 2006. Living with Risk, “A Global Review of Disaster Reduction
Initiatives”. Buku terjemahan oleh MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana
Indonesia), Jakarta.
Anonim, 2009, Terminologi Pengurangan Risiko Bencana, dengan asistensi dari United
Nation for International Disaster Reduction (UNISDR), Asian Disaster Reduction
and Response Network (ADRRN), Kantor Asia dan Pasifik, Bangkok. Translasi
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 13
dan Adaptasi Terminologi Edisi Bahasa Indonesia oleh Humanitarian Forum,
Indonesia.
---------, 2007, UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Republik
Indonesia.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Padang Sago dalam Angka,
2011.
Blackwood, Evelyn, 2000, Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran
Village, Rowman and Littlefield Publishers, USA.
Cuttler, M.D Howard., Dalai Lama, 2004, The Art of Happiness, PT SUN, Jakarta,
diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono Widodo, Seni Hidup Bahagia; Buku
petunjuk untuk hidup.
Denzin, Norman K., Yvonna S Lincoln, 2009, Handbook of Qualitative Research, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Giddens, Anthony, 2009, The consequences of modernity, Kreasi Wacana, Yogyakarta,
diterjemahkan oleh Nurhadi, Konsekuensi-konsekuensi Modernitas.
Griffin, David Ray, Spiritually and Society: Post Modern Visions, terjemahan oleh
Kanisius dalam Visi-visi Post Modern, Spiritualitas dan Masyarakat; Kanisius,
Yosyakarta, 2005
Guba & Lincoln, Berbagai paradigma yang bersaing dalam penelitian kualitatif, dalam
Denzin, Norman K., Yvonna S Lincoln, Handbook of Qualitative Research,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hasbullah, Jousairi, 2006, Social Capital; Menuju Keunggulan Budaya Manusia
Indonesia, MR-United Press, Jakarta.
Hunter, James Davidson., Stephen C Ainlay, 1986, Making Sense of Modern Times; Peter
L Berger and the Vision of Interpretive Sociology, Routledge & Kegan Paul Inc,
New York.
Hannigan, John, 2006, Environmental Sociology, Second edition, Routledge, USA.
Indian Ocean Tsunami and International Cooperation, East Asian Strategic Review 2006,
Chapter 2.
ISDR, 2004, Living with Risk ” A Hundred Positive Examples of How People are Making
The World Safer” United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.
Joas, Hans, 2006, Knowledge, Power, and Consensus, dalam McWilliams, Wilson Carey,
The Active Society Revisited, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, USA.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 14
Jones, PIP, 1998, Pengantar Teori-teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-
Modernisme, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Kasim, Muslim, 2010, Getar Episentrum di Ranah Minang; Penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Gempabumi di Kabupaten Padang Pariaman, Indomedia,
Bogor.
Lash, Szerszynski., Wynne, 2010, Risk, Environment & Modernity Towards a New
Ecology, Sage Publication Ltd, California.
Lawang, Rober. M, 2005, Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik; Suatu Pengantar,
Fisip UI Press, Depok.
Loomis Charles P., 2002, Community and Society, David & Charles, Brunel House, Forde
Close, Newton Abbot, Devon TQ12 4PU, United Kingdom.
Mehta, Michael. D., Eric Ouellet, 1995, Environmental Sociology, Theory and Practice,
Captus Press Inc, Canada.
McWilliams, Wilson Carey, 2006, The Active Society Revisited, Wilson Rowman &
Littlefield publishers, Inc, USA.
M.S Amir, 2011, Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Citra Harta
Prima, Jakarta.
Muhadjir, Noeng, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta.
Naim, Mochtar, 2013, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Panuh, Helmy, 2012, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah
Adat di Sumatera Barat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana
Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012.
----------, Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa
Bumi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, RPJMD Kab. Padang Pariaman, 2010-2015.
----------Laporan Korban Gempa Kab. Pd. Pariaman 30 September 2009.
Pemerintah Nagari Batu Kalang, R PJMD dan RKP Nagari Batu Kalang 2011-2015.
----------, Rekap Data Kerusakan Bangunan Rumah Nagari Batu Kalang 2009.
----------, Laporan Dampak Gempa Nagari Batu Kalang 30 September 2009.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 15
Pemerintah Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Rencana Aksi
Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014.
Poloma, Margaret M, 2010, Sosiologi Kontemporer, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah
Yasogama dari judul asli Contemporary Sociological Theory, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Pranoto, 2011, Lessons Learned Pembelajaran Rehab Rekon Pasca Gempa di Sumatera
Barat 30 September 2009; Building Back Better.
Priyono, Herry, 2002, Anthony Giddens; Suatu Pengantar, Kepustakaan Populer
Gramedia.
Putnam, Robert D, 2002, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in
Contemporary Society, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Inc, New York.
Reason, Peter, 2009, Tiga Pendekatan dalam Penelitian Partisipatif dalam Denzin,
Norman K & Lincoln Yvonna S, Handbook of Qualitative Research, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Redclift, Michael., Graham Woodgate, 2004, The International Handbook of
Environmental Sociology, Second Edition, MPG Books Group, UK.
Ritzer, George, 2010, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Ritzer, George,. Barry Smart, 2011, Handbook Teori Sosial, Diadit Media, Jakarta.
Ritzer, George., Douglas.J Goodman, 2010, Teori Sosiologi Modern, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta.
Rodríguez, Quarantelli., Dynes, 2007, Handbook of Disaster Research, Springer, USA.
Rojas, Fabio, 2006, The Sybernetic Institutionalist, dalam McWilliams, Wilson Carey, The
Active Society Revisited, Wilson Rowman & Littlefield publishers, Inc, USA.
Smith, Anthony Oliver., Susanna M Hoffman, 1999, The Angry Earth; Disaster in
Anthropological perspective, Routledge, New York.
----------, 2001, Catasthrophe and Culture; The Anthropology of Disaster, School of
Disaster Research Press, OXFORD.
Stake, Robert E, 2009, Studi Kasus dalam Denzin, Norman K & Lincoln Yvonna S,
Handbook of Qualitative Research, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Stallings, Robert A, 1997, Sociological Theories and Disaster Studies, University of
Delaware Disaster Research Center.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 16
Suparjan dan Suyatno, 2003, Pengembangan Masyarakat; dari Pembangunan sampai
Pemberdayaan, Aditya Media, Yogyakarta.
Wisner et. al., 2003, At Risk; Natural Hazards, Pepople’s vulnerability and Disasters,
Second Edition, Routledge, New York.
B. Jurnal/Karya Ilmiah/Kertas Kerja/Laporan
Abdulah, Irwan, 2008, Konstruksi dan Reproduksi Sosial Atas Bencana Alam, Yogyakarta.
Anonim, 2010, Laporan Khusus Penanganan Bencana Gempa Bumi di Prov. Sumatera
Barat Tanggal 27 Oktober.
--------, 2007, Laporan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana Gempabumi di
Provinsi Sumatera Barat 6 Maret 2007, Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS).
--------, 2004, Laporan Preliminary Damage and Loss Assessment, The December 26, 2004
Natural Disasters.
---------, 2009, Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah
Pascabencana Gempa Bumi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011,
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
--------, 2007, West Sumatra and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss and Preliminary
Needs Assessment.
Coleman, James S, 1994, Foundations of Social Theory, Harvard University, USA.
---------, 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, Supplement:
Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the
Analysis of Social Structure, The American Journal of Sociology, Vol. 94.
Drabek Thomas E, 2006, Social Problems Perspectives, Disaster Research and Emergency
Management: Intellectual Contexts, Theoretical Extensions, and Policy
Implications.
Drabek, 2005, Sociology, Disasters and Emergency Management: History, Contributions,
and Future Agenda, Department of Sociology and Criminology, University of
Denver.
Dunlap, Riley. E and Catton, William. R, 1979, Environmental Sociology, Annual Review
of Sociology, Vol 5.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 17
Dynes, Russel, 2006, Social Capital: Dealing with Community Emergencies, The Journal
of The Naval Postgraduate School Center for Homeland Defense and Security,
Volume II No. 2: July.
Fatimah dan Budhi, 2009, Kerentanan dan Dampak Bencana; Potret Gender Sumatera
Barat, Desember.
Fischer Henry W, 2003, The Sociology of Disaster: Definitions,Research Questions, &
Measurements Continuation of the Discussion in a Post-September 11
Environment, Sociology Department, Millersville University of Pennsylvania,
USA.
Kreps, G. A, 1985, Disaster and the Social Order, Source: Sociological Theory, Vol. 3,
No. 1.
---------, 1994, Sociological Inquiry And Disaster Research, Department of Sociology,
College of William and Mary, Williamsburg, Virginia.
Ka‟bati, 2009, Perempuan-perempuan Ordo Ulakan, Srinthil, Media Perempuan
Multikultural, Edisi 17.
Maarif, Syamsul, 2010, Bencana dan Penanggulangannya; Tinjauan dari Aspek
Sosiologis, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana.
Nakagawa, Yuko., Rajib Shaw, 2004, Social Capital: A Missing Link to Disaster Recovery,
United Nation Center for Regional Development (UNCRD) dalam International
Journal of Mass Emergencies and disasters, Vol. 22, No. 1, Maret.
Natsir, 2011, Peranan Surau Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Di Padang
Pariaman Sumatera Barat (Surau Syaikh Burhanuddin), Jurusan Pendidikan Luar
Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
Pretty, Jules., Hugh Ward, 2001, Social Capital and The Environment, World
Development Vol. 29, No. 2, Elseiver Science Ltd, Great Britain.
Putnam, Robert D, 1995, Bowling Alone: America's Declining Social Capital, The Johns
Hopkins University Press, Journal of Democracy 6:1. March 21.
---------, 2004 , The Prosperous Community The American Prospect vol. 4 no. 13,
---------, Social Capital: Measurement and Consequences, Kennedy School of
Government, Harvard University.
---------, 2004, Education, Diversity, Social Cohesion and “Social Capital” Note for
Discussion, Meeting of OECD Education Ministers, Dublin.
Quarantelly, E.L, 1989, Conceptualizing Disasters from a Sociological Perspective,
International Journal of Mass Emergencies and Disasters, Disaster Research
Center, University of Delaware, USA, November, Vol 7 No. 3.
Artikel Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas Padang 18
---------, 2007, Theory Award Lecture presented at the annual meeting of the American
Sociological Association, New York City, New York, August.
Quarantelly, EL and Perry, 2005, What is a Disaster? New Answers to Old Questions,
International Research Committee on Disasters, USA.
Rodrigues, Quarantelly and Dynes, 2007, Hand Book of Disaster Research, Springer, New
York, USA.
C. Website
http://bundokanduang.wordpress.com/ (Diunduh pada tanggal 15 April 2013 pukul 08.36)
http://dictionary.reference.com/browse/trust (Dinduh pada tanggal 9 Juni 2013 pukul
14.27)
http://id.wikipedia.org/wiki/Bundo_Kanduang/ , (Diunduh pada tanggal 15 April 2013
pukul 07.58)
http://padangpariamankab.go.id/ , (Diunduh tanggal 01 Mei 2013 pukul 16.58)
http://www.socialcapitalresearch.com/, (Diunduh pada tanggal 19 Januari 2012 pukul: 0.54
http://www.imadiklus.com/, (Diunduh tanggal 7 November 2012 pukul 16.05)
http://www.infed.org/thinkers/putnam.htm, (Diunduh tanggal 12 Februari 2012 pukul
13.56)
http://www.scribd.com/, (Diunduh tanggal 6 November 2012 pukul 15.55)
http://www.surabaya.go.id/, (Diunduh pada tanggal 15 April 2013 pukul 09:14)
D. Surat Kabar
Teguh, Tradisi Julo-julo di Tengah Ekonomi Modern, Harian Haluan, Selasa, 26 April
2011.