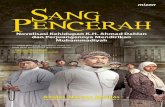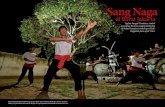nilai religius dalam novel sang pencerah karya akmal nasery ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
Transcript of nilai religius dalam novel sang pencerah karya akmal nasery ...
i
NILAI RELIGIUS DALAM NOVEL SANG PENCERAHKARYA AKMAL NASERY BASRAL DAN SKENARIO
PEMBELAJARANNYA DI KELAS XI SMA
SKRIPSI
Disusun sebagai Salah Satu Syaratuntuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
OlehEni Kusrini
NIM 082110095
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
2012
iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN
MOTO
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan (QS al Mujadallah 11).
PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Bapak dan Ibu tercinta atas doa, bimbingan,
kasih sayang dan cintanya yang selalu
mengiringi perjalanan hidupku;
Skripsi ini ku hadiahkan untuk:
1. Kakak-kakakku yang selalu memberikan
motivasi.
2. Teman-teman seangkatanku, periode
2008/2009.
v
PRAKATA
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini
berjudul “Nilai Religius dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral
dan Skenario Pembelajarannya di kelas XI SMA”, yang disusun sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan studi akhir Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Purworejo.
Skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak mendapat bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih yang setulus-tulusnya kepada:
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah memberikan izin
kepada penulis untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Purworejo dari
awal sampai akhir studi.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Purworejo.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah
memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. M. Fakhrudin, M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Umi Faizah,
M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing,
vii
ABSTRAK
Eni Kusrini. “Nilai Religius dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal NaseryBasral dan Skenario Pembelajaran di kelas XI SMA”. Skripsi. Program StudiPendidikan Bahasa dan Sastra Indonesiaa. Universitas MuhammadiyahPurworejo. 2012.
Dalam penelitian ini dibahas (1) bagaimanakah struktur novel SangPencerah Karya Akmal Nasery Basral? (2) Bagaimanakah nilai religius novelSang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral? (3) Bagaimanakah skenariolangkah-langkah pembelajaran struktur dan nilai religius novel Sang PencerahKarya Akmal Nasey Basral di kelas XI SMA? Tujuan dalam penelitian ini adalah(1) mendeskripsikan struktur novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral,(2) mendeskripsikan nilai religius novel Sang Pencerah Karya Akmal NaseryBasral, (3) mendeskripsikan skenario langkah-langkah pembelajaran struktur dannilai religius novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasey Basral di kelas XI SMA.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori religius sastra yangdikemukakan oleh Mangunwijaya (1994: 27) yakni, (1) hubungan manusiadengan Tuhannya, (2) hubungan manusia dengan manusia, dan (3) hubunganmanusia dengan alam sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah teks novel Sang Pencerahkarya Akmal Nasery Basral.
Fokus penelitian berupa hubungan manusia dengan Tuhan, manusiadengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya pada novel Sang Pencerahkarya Akmal Nasery Basral dan skenario pembelajaran di kelas XI SMA. Teknikpengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi. Teknik yangdigunakan untuk menganalisis data dalam novel Sang Pencerah karya AkmalNasery Basral adalah teknik analisis isi. Teknik yang digunakan penulis untukmenyajikan hasil analisis adalah teknik penyajian informal (Sudaryanto, 1993:145).
Dari hasil penelitian terbukti bahwa (1) Struktur novel Sang Pencerahkarya Akmal Nasery Basral yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latardan amanat secara padu membangun cerita yang mempunyai nilai estetis dan nilaireligius, (2) nilai religius novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basralmencakup tiga aspek yaitu: (a) hubungan manusia dengan Tuhan meliputikewajiban salat, tawakal, jujur, syukur, pemimpin harus bertanggung jawab, Islamadalah agama yang membawa rahmat, dan tidak boleh taklid dalam beragama, (b)hubungan manusia dengan manusia hubungan yang baik antara Darwis denganbapak/ibu, menjalin pertemanan, menghormati guru, menyantuni anak yatim, danmenikah, dan (c) hubungan manusia dengan alam sekitar yaitu bahwa pohon tidakuntuk disembah. Nilai-nilai religius itu dikemas dalam bentuk cerita yang indahdan tidak bersifat menggurui, (3) skenario pembelajaran nilai religius pada novelSang Pencerah karya Akmal Nasery Basral terdiri atas enam langkah yakni (a)pelacakan pendahuluan, (b) pendekatan sikap praktis, (c) introduksi, (d)penyajian, (e) diskusi, dan (f) pengukuhan.
Kata kunci : Nilai Religius, Novel Sang Pencerah, Skenario Pembelajaran
viii
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL............................................................................................................. iPENGESAHAN ............................................................................................... iiPERNYATAAN............................................................................................... iiiMOTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... ivPRAKATA....................................................................................................... viABSTRAK ....................................................................................................... viiDAFTAR ISI.................................................................................................... viiiDAFTAR TABEL ........................................................................................... xDAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1B. Penegasan Istilah...................................................................... 10C. Rumusan Masalah .................................................................... 11D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................. 12E. Sistematika Skripsi................................................................... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS ................... 16A. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 16B. Kajian Teoretis ......................................................................... 18
1. Struktur ............................................................................. 182. Religiusitas dalam Karya Sastra........................................ 263. Skenario Pembelajaran Sastra di SMA ............................. 28
BAB III METODE PENELITIAN............................................................... 41A. Objek Penelitian ....................................................................... 41B. Fokus Penelitian ....................................................................... 41C. Sumber Data............................................................................. 41D. Instrumen Penelitian................................................................. 42E. Teknik Pengumpulan Data....................................................... 42F. Teknik Analisis Data................................................................ 43G. Teknik Penyajian Data ............................................................. 44
BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA ............................... 45A. Penyajian Data ......................................................................... 45
1. Tabel Struktur Novel Sang Pencerah karyaAkmal Nasery Basral.......................................................... 45
2. Tabel Nilai Religius Novel Sang Pencerah karyaAkmal Nasery Basral.......................................................... 46
3. Skenario Pembelajaran Novel Sang Pencerah karyaAkmal Nasery Basral ......................................................... 46
ix
B. Pembahasan Data ..................................................................... 481. Struktur Novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral ....................................................... 482. Nilai Religius Novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral ........................................................ 101a. Hubungan manusia dengan Tuhan ............................. 102b. Hubungan manusia dengan manusia .......................... 108c. Hubungan manusia dengan alam ................................ 112
3. Skenario Pembelajaran Novel Sang Pencerah karya AkmalNasery Basral ................................................................... 112
BAB V PENUTUP...................................................................................... 130A. Simpulan ................................................................................. 130B. Saran ........................................................................................ 132
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
1. Tabel Struktur Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral .......... 45
2. Tabel Nilai Religius Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral 46
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Sinopsis
Lampiran 2. Biografi Pengarang
Lampiran 3. Daftar Tabel
Lampiran 4. Silabus
Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi
1
BAB IPENDAHULUAN
Pada bab ini dikemukakan lima hal pokok, yaitu latar belakang masalah,
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika skripsi.
A. Latar Belakang Masalah
Sastra merupakan sebuah sarana yang sering dipergunakan untuk
mencetuskan pendapat-pendapat yang hidup di dalam masyarakat. Hasil karya
sastra dapat berbentuk “lirik” (puisi), “epik” (prosa), dan “dramatic” (drama).
Cerita rekaan yang berbentuk prosa, mengandung fiksi atau daya khayal.
Cerita rekaan ialah cerita yang sengaja dikarang oleh seorang sastrawan untuk
dipahami oleh para pembaca (Baribin, 1985: 5-9).
Karya imajiner adalah karya sastra yang bersifat rekaan/ khayalan,
sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu
dicari kebenarannya. Sebagai sebuah karya imajiner, fiksi menawarkan
permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Fiksi
menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan
lingkungan dan sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya
dengan Tuhan.Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi dan reaksi
pengarang terhadap lingkungan. Fiksi merupakan karya imajinatif yang
dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya
seni (Nurgiyantoro, 2010: 2-3).
1
2
Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang berasal dari
imajinasi pikiran pengarang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
Karya sastra menampilkan gambaran kehidupan sosial yang nyata di dalam
masyarakat. Karya sastra merupakan hasil perpaduan harmonis antara kerja
perasaan dan pikiran. Karya sastra tidak hanya mementingkan isi, juga tidak
hanya mengutamakan bentuk. Karya sastra diciptakan pengarang bukan
sekadar untuk menghibur, melainkan juga untuk menyampaikan nasihat-
nasihat pendidikan.
“Novel dibangun dari sejumlah unsur, dan setiap unsur salingberhubungan dan saling menentukan, yang kesemuanya itu akanmenyebabkan novel tersebut menjadi sebuah karya yang bermaknahidup. Di pihak lain, tiap-tiap unsur pembangun novel hanya akanbermakna jika ada dalam kaitannya dengan keseluruhan”(Nurgiyantoro, 2010: 31).
Salah satu landasan untuk memahami nilai religius karya sastra adalah
dengan menganalisis struktur karya sastra itu terlebih dahulu. Hal ini
dilakukan untuk memudahkan dan mengetahui serta memahami cerita dalam
karya fiksi (novel).
Fiksi mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para
tokoh sesuai dengan pandangannya tentang moral. Moral dalam karya sastra
dapat dipandang sebagai amanat, pesan, dan message. (Nurgiyantoro, 2010:
321).
Hubungan antara sastra dengan nilai religius sangat erat. Hal ini
didasarkan pada pendapat Mangunwijaya (1982: 15), yaitu semua sastra
adalah religius. Unsur religius dan keagamaan dalam karya sastra menjadikan
karya sastra itu tumbuh dari sesuatu yang religius.
3
Karya sastra merupakan salah satu wujud dari bentuk penyampaian
nilai moral dan budi pekerti yang diamanatkan pengarang lewat tokoh cerita.
Tidak mengherankan jika karya sastra sangat menarik perhatian pembaca yang
menginginkan pengalaman sosial kemasyarakatan khususnya nilai-nilai
religius.
Nilai religius adalah norma keagamaan yang dipegang sebagai
pedoman dalam hidup. Pedoman hidup orang muslim adalah Alquran yang
wajib diimani. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Yusuf
ayat 111.
Artinya:
"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi
orang-orang yang mempunyai akal. Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-
buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang
beriman” (QS Yusuf ayat 111).
Dijelaskan lebih lanjut bahwa Alquran merupakan pedoman hidup bagi
manusia terdapat dalam surat An Nahl ayat 89.
4
Artinya:
"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
yang berserah diri” (QS An Nahl ayat 89).
Nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel sangat penting diteliti
untuk memperoleh pengetahuan pesan-pesan moral bahkan sering terjadi
munculnya norma-norma baru dalam masyarakat. Seseorang dikatakan
religius jika mempunyai moral akhlak yang baik yang dapat ditunjukkan
dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.
Pengarang novel Sang Pencerah adalah seorang laki-laki yang
bernama Akmal nasery Basral. Dia adalah seorang wartawan dan sastrawan
Indonesia. Kumpulan cerpen pertamanya Ada Seseorang di Kepalaku Yang
Bukan Aku (2006) yang terdiri dari 13 cerpen. Sebagai wartawan dia pernah
bekerja untuk majalah mingguan Gatra (1994-1998), Gamma (1999), majalah
Tempo (2004-sekarang). Dia dapat memaparkan suatu nilai yang kreatif dan
berbobot dengan menggunakan bahasa sederhana yang terkadang masih lekat
dengan Jawa.
Sang Pencerah merupakan novel karya Akmal Nasery Basral yang
diadaptasi dari scenario film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung
5
Bramantyo. Novel Sang Pencerah berkisah tentang kehidupan Kiai Ahmad
Dahlan serta perjuangannya dalam mendirikan Muhammadiyah. Sepulang dari
Mekah Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang
pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang
melenceng kearah Bid’ah dan sesat. Melalui Langgar atau Suraunya Ahmad
Dahlan mengawali pergerakan dengan arah kiblat yang salah di Masjid
kauman yang menyebabkan kemarahan seorang Kiai yakni Kiai
Kamaludiningrat sehingga Surau Kiai Ahmad Dahlan dirobohkan karena
dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai Kiai
kafir hanya karena membuka sekolah yang menempatkan kursi sebagai tempat
duduk seperti sekolah modern Belanda. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai
kiai Kejawen karena Beliau dekat dengan organisasi Budi Utomo, tetapi
tuduhan tersebut tidak membuat Kiai Ahmad Dahlan surut. Siti Walidah,
Sudja, Hisyam, Sangidu, Fakhrudin dan Dirjo yang setia mendampingi Ahmad
Dahlan.
Dalam Alquran dijelaskan tentang bid’ah yaitu surat Ali Imran ayat 7.
6
Artinya :
“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Alquran) kepada kamu di antara(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Alquran danyang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalamhatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untukmencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnyamelainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kamiberiman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhankami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkansuasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSISDIKNAS, 2003:5).
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum
yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya
dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang
masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam
setiap jenjang pendidikan didasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional
dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan
(Ihsan, 2011: 132).
Novel merupakan karya sastra yang dapat digunakan dalam
pembelajaran sastra. Karya sastra khususnya novel mempunyai peran yang
sangat besar dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak didik
karena pelajaran sastra dapat membantu siswa dalam memahami dan
mengekspresikan sebuah karya sastra dengan baik. Selain untuk
7
mengembangkan karakter siswa, novel juga dapat menumbuhkan minat baca
siswa, sehingga siswa tertarik untuk membaca dari awal sampai akhir serta
dapat memahami isi dari novel tersebut.
Pembelajaran sastra merupakan bagian dari kegiatan pendidikan. Oleh
karena itu, segala aspek pembelajaran sastra seharusnya diarahkan pula demi
tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran sastra adalah untuk
meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Siswa
diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai tentang sastra dan sikap
positif terhadap karya sastra.
Melalui kegiatan pembelajaran sastra di SMA khususnya, guru dan
masyarakat mengharapkan agar siswa memiliki wawasan yang memadai
tentang sastra, bersikap positif terhadap sastra serta mampu mengembangkan
wawasan, kemampuan dan sikap positifnya lebih lanjut.
Pembelajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila
cakupannya meliputi 4 manfaat, yaitu: membantu keterampilan berbahasa,
meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, serta
menunjang pembentukan watak (Rahmanto, 1988:16). Berdasarkan tujuan
tersebut, maka sastra merupakan hal penting yang perlu diajarkan di sekolah
karena dapat berperan sebagai media pendidikan moral dan menggugah
perasaan untuk lebih peka terhadap kehidupan sekitarnya.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional
yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan
(Mulyasa, 2011: 19). KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum
8
untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan suatu paradigma
baru yang dapat memberikan suatu perbaikan terhadap kualitas pendidikan.
Dalam KTSP mempunyai ciri mengenai kebebasan pengembangan bahan ajar
bagi pendidik atau guru dalam memilih bahan dan pengembangan bahan
(Muslich, 2009: 17). Kualitas dan keberhasilan belajar peserta didik sangat
dipengaruhi oleh kemampuan dan ketetapan pendidik memilih dan
menggunakan metode. Penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
pada pembelajaran kelas XI semester I yang sesuai dengan judul “Nilai
Religius dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral dan
Skenario Pembelajarannya di Kelas XI SMA”, adalah sebagai berikut;
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Membaca
Memahami berbagai hikayat, novel
Indonesia/novel terjemahan
Menganalisis unsur-unsur intrinsik
dan ekstrinsik novel Indonesia/
terjemahan.
Pembelajaran sastra berdasarkan KTSP, mempunyai alokasi waktu 2 x
45 menit setiap kali pertemuan. Struktur dan nilai religius yang terkandung di
dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral sesuai dengan
kurikulum dan perkembangan peserta didik di SMA kelas XI semester I.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menulis judul “Nilai Religius
dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral dan Skenario
9
Pembelajarannya di Kelas XI SMA”, sebagai bahan penelitian dengan alasan
sebagai berikut:
1. Karya-karya Akmal Nasery Basral telah banyak ditulis dan yang
diterbitkan. Salah satu karya Akmal Nasery Basral adalah novel Sang
Pencerah menjadi materi yang menarik untuk dikaji. Beberapa pendapat
mengemukakan tentang keunggulan Sang Pencerah :
a. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta) berkata “Dengan melihat warisan yang
ditinggalkan, sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk mengenal
kebesaran sosok Ahmad Dahlan dalam sejarah Indonesia. Lewat novel
ini sisi-sisi manusiawinya digambarkan dengan sangat indah dan
menggugah. Siapapun yang menbaca novel ini pasti akan terinspirasi
dan tercerahkan”.
b. Abdul Mu’ti (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah) berkata
“Novel ini mampu menghadirkan sosok K.H. Ahmad Dahlan, pendiri
Muhammadiyah, seorang yang sedikit bicara tetapi kaya gagasan,
teguh hidup sederhana tetapi mampu mengembangkan amal yang
mengubah dunia, suka berdebat tetapi hangat bersahabat. Dengan gaya
bahasa yang mengalir, novel ini menuntun pembaca menapaki jalan
kehidupan tanpa harus menggurui. Layak dibaca bagi para pendidik,
orangtua, tokoh agama dan siapa saja yang ingin menimba kearifan”.
c. Hanung Bramantyo (Sutradara film Sang Pencerah) berkomentar
“Novel ini mengungkap sisi manusiawi seorang Ahmad Dahlan. Tidak
10
mudah dan butuh keberanian seorang penulis. Siapapun dia, seorang
tokoh sebaiknya dikisahkan secara apa adanya”.
2. Setelah membaca novel Sang Pencerah penulis menemukan aspek-aspek
religius dalam novel tersebut sehingga perlu dianalisis.
3. Belum ada penelitian tentang nilai religius novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral yang diteliti oleh mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Purworejo untuk pembelajaran sastra.
B. Penegasan Istilah
Penelitian ini berjudul “Nilai Religius dalam Novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI SMA”
dan agar tidak menjadi salah tafsir terhadap judul penelitian di atas, berikut ini
disampaikan penjelasan beberapa istilah pokok yang dipakai dalam judul
penelitian sebagai berikut:
1. Nilai Religius
Nilai religius adalah nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra fiksi
berupa penentuan manusia yang berhati nurani, berakhlak mulia atau saleh
ke arah segala makna yang baik (Mangunwijaya, 1988: 15). Nilai religius
adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa
ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nilai
religius juga diartikan sebagai norma keagamaan yang dipegang sebagai
pedoman dalam hidup.
11
2. Skenario
Skenario adalah rencana berupa langkah demi langkah yang tertulis
secara terperinci yang digunakan sebagai acuan dalam proses interaksi
antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Pembelajaran
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur
manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran dan manusia terlibat dalam
system pembelajaran yang terdiri dari siswa, guru,dan tenaga lainnya
(Hamalik, 2011: 57). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam
pembelajaran terkandung 5 konsep yaitu: interaksi, peserta didik, pendidik,
sumber belajar dan lingkungan belajar (UU SISDIKNAS, 2003: 2).
Jadi, maksud judul skripsi “Nilai Religius dalam Novel Sang
Pencerah Karya Akmal Nasery Basral dan Skenario Pembelajarannya di
Kelas XI SMA” adalah penelitian terhadap aspek-aspek religius novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral dan proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar untuk siswa di kelas XI SMA.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimanakah aspek struktural yang terkandung dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
12
2. Bagaimanakah nilai religius yang terkandung dalam novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral?
3. Bagaimanakah skenario langkah-langkah pembelajaran nilai religius novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral di kelas XI SMA?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian dengan judul “Nilai Religius dalam novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral dan Skenario Pembelajarannya di Kelas XI
SMA” bertujuan untuk:
a. mendeskripsikan aspek struktural yang terkandung dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral;
b. mendeskripsikan nilai religius yang terkandung dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral;
c. mendeskripsikan skenario langkah-langkah pembelajaran nilai religius
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral di kelas XI SMA.
2. Kegunaan Penelitian
1) Segi Teoretis
Dari segi teoretis, penelitian ini bermanfaat antara lain:
a. Menambah khazanah penelitian sastra
b. Mengaplikasikan teori religius di dalam sebuah novel
c. Dapat memperkaya wawasan dibidang Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, dan hasilnya dapat digunakan untuk
13
mengembangkan teori religius yang sebelumnya digunakan sebagai
sumber atau bahan pembelajaran.
2) Segi Praktis
a) Manfaat bagi siswa
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan
dan mengembangkan pemahaman siswa tentang nilai religius karya
sastra yang terdapat dalam novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral pada khususnya, dan meningkatkan kreativitas dan
keberanian siswa dalam berpikir.
b) Manfaat bagi guru
Penelitian ini untuk memperkaya khazanah metode dan
strategi dalam pembelajaran tentang penelitian novel, untuk dapat
memperbaiki metode mengajar yang selama ini digunakan, agar
dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan
tidak membosankan, dan dapat mengembangkan keterampilan guru
bahasa dan sastra Indonesia khususnya dalam menerapkan
pembelajaran religius karya sastra novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral.
c) Manfaat bagi sekolah
Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
rangka memajukan dan meningkatkan prestasi sekolah yang dapat
disampaikan dalam pembinaan guru ataupun kesempatan lain
bahwa pembelajaran struktur karya sastra novel khususnya novel
14
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral sebagai bahan
pencapaian hasil belajar yang maksimal.
E. Sistematika Skripsi
Sistematika skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
skripsi yang disusun. Skripsi ini terdiri dari lima bab, pada bagian awal terdiri
dari sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan,
pernyataan, moto dan persembahan, prakata, daftar isi, dan abstrak.
Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.
Bab II tinjauan pustaka dan kajian teoretis. Tinjauan pustaka berisi
kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu
yang berhubungan dengan topik penelitian ini di antaranya Suyud (2005),
Purwanti (2010), dan Milllati (2011). Dalam kajian teoretis disajikan (1)
hubungan manusia dengan Tuhannya, (2) hubungan manusia dengan
manusia, dan (3) hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian ini berisi objek
penelitian, fokus penelitian, sumber data, instrument penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis
data.
Bab IV berisi penyajian data dan pembahasan. Pada bab ini, penulis
menyajikan dan membahas data yang diambil dari novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral mengenai struktur, nilai religius dan skenario
15
pembelajaran novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral di kelas XI
SMA.
Bab V berisi penutup. Pada bab ini penulis menyimpulkan
pembahasan data dan memberikan saran-saran yang relevan dengan
kesimpulan tersebut. Selain itu, penulis juga melampirkan sinopsis novel Sang
Pencerah, biografi pengarang, dan daftar pustaka.
16
BAB IITINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS
Pada bab ini dikemukakan dua hal pokok, yaitu tinjauan pustaka dan
kajian teoretis.
A. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis untuk
membandingkan terhadap kajian terdahulu dengan kajian yang akan penulis
lakukan sehingga diketahui perbedaan dan kesamaan yang khas antara kajian-
kajian tersebut.
Penelitian melalui pendekatan religius terhadap sastra telah banyak
dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Beberapa diantaranya yaitu: (1) Suyud (2007) “Religiositas dalam Novel
Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari”, (2) Purwanti (2010) “Nilai-
Nilai Religious dalam Novel Tasawuf Cinta karya M. Hilmi As’ad”, dan (3)
Millati (2012) berjudul “Nilai-Nilai Religius dalam Novel Ketika Cinta
Bertasbih I karya Habiburrahman El-Shirazy dan Relevansi Pembelajarannya
di SMA”.
Hasil penelitian Suyud (2007) berjudul “Religiositas dalam Novel
Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari”. Dalam penelitian ini,
Suyud membahas struktur dan nilai religiositas dalam novel Lingkar Tanah
Lingkar Air. Penelitian yang dilakukannya mempunyai kesamaan dan
16
17
perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan,
keduanya membahas nilai religius novel. Perbedaannya, Suyud menganalisis
nilai religiositas dan struktural tanpa memberikan gambaran tentang
pembelajarannya di SMA. Perbedaan yang lain terdapat pada subjek
penelitian, penelitian Suyud mengambil subjek novel Lingkar Tanah Lingkar
Air karya Ahmad Tohari”, sedangkan penulis pada novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral.
Skripsi Purwanti (2010) berjudul “Nilai-Nilai Religiositas dalam
Novel Tasawuf Cinta karya M.Hilmi As’ad. Penelitian Purwanti bertujuan
untuk mengetahui nilai-nilai religiositas dalam Novel Tasawuf Cinta karya
M.Hilmi As’ad khususnya nilai-nilai Islam. Penelitian ini menunjukkan
adanya hubungan antarstruktur yaitu hubungan antara tokoh dengan latar,
hubungan tokoh dengan alur, hubungan antara tema dengan tokoh, dan
hubungan antara alur dengan latar, sedangkan kandungan nilai-nilai religius
yang Islami dalam novel Tasawuf Cinta karya M.Hilmi As’ad yaitu (1) nilai
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan Tuhannya,
(2) nilai peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hubungan
horizontal manusia dengan manusia, dan (3) nilai peribadatan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
Skripsi Millati (2012) berjudul “Nilai-Nilai Religius dalam Novel
Ketika Cinta Bertasbih I karya Habiburrahman El-Shirazy dan Relevansi
Pembelajarannya di SMA”. Penelitian yang dilakukan oleh Millati bertujuan
untuk mengetahui nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel Ketika
18
Cinta Bertasbih I karya Habiburrahman El-Shirazy, dan mengetahui relevansi
novel Ketika Cinta Bertasbih I dengan pembelajaran di SMA. Teori yang
digunakan dalam penelitian Millati adalah teori yang dikemukakan oleh
Mangunwijaya yang mengemukakan bahwa nilai religius mencakup tiga
aspek, yaitu (1) hubungan manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan
manusia, dan (3) manusia dengan alam sekitarnya. Pembelajaran yang
digunakan adalah pembelajaran PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan). Terdapat kesamaan antara penelitian
Millati dengan analisis penulis, yaitu teori yang digunakan menggunakan
teori Mangunwijaya bahwa nilai religius mencakup tiga aspek yaitu (1)
hubungan manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan manusia, dan (3)
manusia dengan alam sekitarnya.
Dalam penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian
tentang “Nilai Religius dalam Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery
Basral dan Skenario Pembelajarannya di kelas XI SMA” sepengetahuan
penulis belum ada yang mengkaji apabila ditinjau berdasarkan nilai religius.
B. Kajian Teoretis
1. Stuktur Karya Sastra
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami karya
sastra yang berbentuk prosa adalah pendekatan struktural, yang berarti
memahami karya sastra dengan memperhatikan struktur atau unsur-unsur
pembentuk karya sastra.
19
Suatu karya sastra dibentuk oleh unsur-unsur yang membentuknya.
Analisis struktural merupakan prioritas pertama sebelum diterapkannya
analisis yang lain. Unsur-unsur struktur karya sastra meliputi tema, tokoh
dan penokohan, alur, latar, amanat dan pusat pengisahan. Analisis
struktural sangatlah tepat untuk meneliti dan mengungkapkan unsur-unsur
karya sastra dan keterkaitan antarunsur tersebut sebagai kesatuan makna.
a. Tema
Di bawah ini beberapa pendapat mengenai tema yang
dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut:
1) Nurgiyantoro (2011:68) mengatakan, tema merupakan keseluruhan
yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” di
dalam cerita yang mendukungnya.
2) Sudjiman (1986: 50) mengatakan, tema adalah gagasan, ide atau
pikiran utama yang mendasari karya sastra.
Menurut Nurgiyantoro, tema dibedakan menjadi dua bagian
yaitu tema utama yang disebut tema mayor yang artinya makna pokok
yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum karya itu. Tema mayor
ditentukan dengan cara menentukan persoalan yang paling menonjol,
yang paling banyak konflik dan waktu penceritaannya, sedangkan tema
tambahan disebut tema minor. Tema minor merupakan tema yang
kedua yaitu makna yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu
cerita dan diidentifikasikan sebagai makna bagian atau makna
tambahan.
20
Tema adalah ide cerita yang merupakan dasar untuk
pengembangan cerita yang menjiwai seluruh bagian cerita. Kedudukan
tema dalam novel sangat penting, karena tanpa tema sebuah karya
tidak memiliki makna.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema adalah
inti persoalan yang ditampilkan dalam suatu cerita, atau sesuatu yang
menjadi tujuan utama pengarang. Tema juga dapat dipandang sebagai
dasar cerita, gagasan dan dasar umum sebuah karya sastra. Gagasan
dasar umum inilah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang
yang digunakan untuk mengembangkan cerita.
b. Tokoh dan Penokohan
Dalam setiap cerita rekaan, keberadaan tokoh merupakan hal
yang penting. Pada hakikatnya sebuah cerita rekaan merupakan
rangkaian peristiwa yang dialami oleh seorang atau pelaku cerita. Jika
kita membaca sebuah novel atau cerita, akan timbul dalam pikiran kita
tentang tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, sehingga kita akan
membayangkan bagaimana wajah dan sifat-sifat kepribadian tokoh
tersebut.
Setiap tokoh dalam suatu cerita mempunyai ciri-ciri tersendiri
atau watak yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Sudjiman
(1988: 78), tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa
atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Penokohan
mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh karena
21
penokohan dalam sebuah cerita memberikan gambaran yang jelas
kepada pembaca.
Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembaca dan
penyampai pesan, amanat, moral atau sesuatu yang sengaja ingin
disampaikan peangarang kepada pembaca. Penokohan adalah
pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan
dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2010: 165).
1) Tokoh utama dan tokoh tambahan
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritanya
dalam novel yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2010: 176). Tokoh
utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik
sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian.
Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak sentral
kedudukannya dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan
ntuk mendukung tokoh utama (Nurgiyantoro, 2010:177).
2) Tokoh Protagonis dan Antagonis
Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang
salah satu jenisnya secara popular disebut tokoh hero yang
merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal
bagi kita (Nurgiyantoro, 2010: 178). Tokoh antagonis adalah tokoh
yang menyebabkan konflik bagi tokoh protagonist (Nurgiyantoro,
2010: 178).
22
3) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat
Tokoh sederhana adalah adalah tokoh yang hanya memiliki
satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja
(Nurgiyantoro, 2010: 181). Tokoh bulat adalah tokoh yang
memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya,
sisi kepribadian, dan jati dirinya (Nurgiyantoro, 2010: 183).
Menurut Sudjiman, cara pengambaran penokohan yaitu
menggunakan metode analitik dan metode dramatik. Metode
analitik, penokohan memberikan ciri lahir atau fisik maupun lahir
tokoh. Metode dramatik, watak tokoh dapat disimpulkan dari
pikiran, dan lakuan tokoh yang disajikan pengarang.
Dari uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa tokoh
cerita sebagai penyampai tema, sedangkan penokohan merupakan
penggambaran fisik para tokoh cerita.
c. Alur
Sudjiman (1986: 4) mengemukakan bahwa alur atau plot adalah
suatu jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek
tertentu.
Stanton (2007: 26), berpendapat alur adalah cerita yang berisi
urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara
sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya
peristiwa lain.
23
Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2010: 149-150), membedakan
tahapan plot menjadi lima bagian yaitu:
1) Tahap situation (mulai melukiskan suatu peristiwa)
2) Tahap generating circumstances (peristiwa mulai bergerak)
3) Tahap rising action (keadaan mulai memuncak)
4) Tahap climax (mencapai titik puncak)
5) Tahap denouement (pemecahan / penyelesaian suatu peristiwa).
Menurut Sudjiman (1988: 30), struktur alur dapat dibagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut:
(a) Awal(1) Paparan (exposition), berisi peristiwa awal yang
memberikan gambaran masalah yang dihadapi oleh tokohcerita.
(2) Rangsangan (inciting moment), merupakan bagian aluryang mengarah pada terjadinya tindakan awal sang tokoh.
(3) Gawatan (rising action), merupakan bagian dari alur yangmenunjukkan gerak menanjak masalah.
(b) Tengah(1) Tikaian (confict), menggambarkan perbedaan sikap,
keinginan, dan pandangan masalah para tokoh.(2) Rumitan (complication), menunjukkan tikaian yang
semakin tajam dan rumit.(3) Klimaks (climax), menunjukkan ketajaman konflik yang
dihadapi para tokoh.(c) Akhir
(1) Leraian (falling action), menggambarkan mulai cairnyakebekuan dan kekakuan sikap para tokoh yang terjadihingga klimaks.
(2) Selesaian (denaument), memberikan gambaran nasib paratokoh terhadap penyelesaian.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur atau plot adalah
struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun untuk menandai
urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Oleh karena itu, alur
24
atau plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita
berupa kerangka utama cerita dalam pemecahan konfllik yang terdapat
dalam suatu karya sastra.
d. Latar
Suatu cerita rekaan berkisah tentang seorang atau beberapa
tokoh. Peristiwa-peristiwa di dalam cerita tentunya terjadi pada suatu
waktu tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa segala
keterangan dan petunjuk pengacuan yang berkaitan dengan waktu,
ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra yang
membangun latar cerita.
Menurut Sudjiman (1991:480), latar adalah segala keterangan
waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra.
1) Latar Tempat
Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa
yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi.
2) Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan”
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya
fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya dihubungkan dengan
waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan
dengan peristiwa sejarah.
25
3) Latar Sosial
Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan
dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang
diceritakan dalam karya fiksi.
Dari pendapat di atas dapat ditarik simpulan bahwa latar
tempat mengacu pada tempat terjadinya suatu peristiwa di dalam
cerita. Latar waktu mengacu pada saat terjadinya peristiwa-
peristiwa yang diceritakan dalam cerita, sedangkan latar sosial
mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku
kehidupan sosial. Latar dari suatu cerita dapat menimbulkan efek-
efek emosional pada diri tokoh yang dirasakan oleh pembaca,
sehingga pembaca larut dalam cerita. Jadi, menonjolkan latar
waktu dan latar tempat dalam suatu cerita sangat penting.
e. Amanat
Dari sebuah karya sastra dapat diangkat suatu ajaran moral, atau
pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerita
biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan
ajaran moral tertentu.
Amanat pada sebuah karya sastra ditampilkan secara implisit
(tak langsung) ataupun eksplisit (langsung) (Sudjiman, 1988: 57).
26
2. Religiusitas dalam Karya Sastra
a. Pengertian Religius
Dister (dalam Nur Ghufron dan Risnawati, 2010: 167).
mengartikan, religiusitas sebagai keberagaman karena adanya
internalisasi agama ke dalam diri seseorang. Shihab menyatakan,
agama adalah hubungan antara makhluk dengan khalik (Tuhan) yang
berwujud ibadah yang dilakukan dalam sikap keseharian.
Atmosuwito (1989: 123) menyatakan bahwa religius harus
dibedakan dari pengertian agama. Kata religious menurut asalnya
berarti ikatan atau pengikatan diri, sedangkan agama terbatas pada
ajaran-ajaran (doctrines) dan peraturan-peraturan (law).
Mangunwijaya (1988:12) membedakan istilah religi atau
agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjuk aspek formal
yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban,
sedangkan religiusitas mengacu pada aspek religi yang dihayati oleh
individu di dalam hati.
Religiusitas dapat diartikan sebagai pendalaman agama dalam
diri seseorang yang terlihat melalui pengetahuan dan keyakinan
seseorang akan agamanya serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-
hari. Nilai religius adalah nilai-nilai ketuhanan yang diungkapkan
seseorang dengan cara tertentu, karena adanya keterikatan manusia
dengan Tuhan sebagai sumber dari segala kebaikan.
27
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religi adalah
agama, sedangkan religius adalah nilai-nilai ketuhanan yang
berhubungan dengan sikap atau tindakan manusia yang memahami
dan menghayati hidup serta mendorongnya untuk bertingkah laku,
bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Religiusitas
adalah suatu keadan yang ada dalam diri seseorang yang
mendorongnya bertingkah laku dan bersikap sesuai ajaran agamanya
yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari.
b. Nilai Religius Karya Sastra
Nilai religius sebuah karya sastra yaitu seberapa jauh dan
bagaimana memuat nilai religius sehingga novel itu bernuansa
religius. Jika dikaitkan dengan pengarangnya, maka seberapa jauh
pengarang mengungkapkan nilai-nilai religius dalam karya satra yang
diciptakannya.
“Karya sastra fiksi senantiasa menyajikan pesan moral yangberhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan,memperjuangkan hak dan martabat manusia. Sifat-sifat luhurkemanusiaan tersebut pada hakikatnya bersifat universal.Artinya, sifat-sifat itu dimiliki, dan diyakini kebenarannya olehmasyarakat (Nurgiyantoro, 2010: 322)”.
Jenis ajaran moral karya fiksi mencakup masalah yang bersifat
tak terbatas. Secara garis besar persoalan hidup dan kehidupan
manusia dapat dibedakan ke dalam persoalan hubungan manusia
dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam
lingkup sosial termasuk hubungannya dengan lingkungan alam, dan
hubungan manusia dengan Tuhannya.
28
Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat bermacam-
macam jenis dan tingkat intensitasnya. Hal itu tentu saja tidak lepas
dari kaitannya dengan persoalan hubungan antarsesama dan dengan
Tuhan. (Nurgiyantoro, 2010: 323-324).
Dalam novel pasti terkandung pesan moral berupa religius.
Pada dasarnya karya sastra diciptakan untuk menyampaikan pesan-
pesan kepada pembaca. Walaupun pesan moral yang disampaikan
sedikit tetapi masih mengandung pesan moral yang berupa religius
seperti dikatakan Mangunwijaya (1988: 11) bahwa karya sastra pada
dasarnya religius.
Seperti yang dikemukakan Nurgiyantoro (2010: 326) bahwa
pesan moral yang berwujud moral religius, yang bersifat keagamaan
dan kritik sosial banyak ditemukan dalam karya fiksi atau genre sastra
yang lain. Kedua hal tersebut memberikan inspirasi bagi para penulis,
khususnya sastra Indonesia modern.
Dapat disimpulkan bahwa nilai religius dalam karya sastra
(novel) bertujuan untuk memperdalam serta mempermudah hubungan
manusia dengan Tuhan.
3. Skenario Pembelajaran Sastra di SMA
a) Pengertian Pembelajaran Sastra
Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Novel sebagai
salah satu karya sastra sangat memungkinkan untuk diajarkan di
29
sekolah (SMA). Salah satu kelebihan novel sebagai bahan
pembelajaran sastra adalah cukup mudahnya karya sastra tersebut
dinikmati sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam
memahami cerita sesuai perseorangan. Namun tingkat kemampuan
tiap-tiap individu tidak sama (Rahmanto, 1988:66).
Dalam pembelajaran sastra, keterampilan yang dikembangkan
adalah keterampilan yang bersifat indra, yang bersifat penalaran, yang
bersifat efektif, yang bersifat sosial dan yang bersifat religius. Oleh
karena itu, dapat ditegaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan
dengan benar akan dapat menyediakan kesempatan untuk
mengembangkan keterampilan sehingga pembelajaran sastra tersebut
dapat mendekati arah dan tujuan dalam arti yang sesungguhnya.
Kajian religius sastra novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral dan pembelajarannya di SMA dapat sebagai pelengkap
atau pendukung pembelajaran agama yang diajarkan di sekolah seperti
pembelajaran tentang Alquran dan pelajaran ibadah. Namun, tingkat
kemampuan individu tidak sama. Oleh karena itu, guru diharapkan
mampu menyajikan pembelajaran novel dengan baik dan menarik
sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap peserta didik.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
sastra adalah suatu aktivitas atau kegiatan pembelajaran untuk
menyusun dan menguji suatu rencana atau program yang
memungkinkan timbulnya proses belajar pada diri siswa sehingga
30
siswa mampu memahami masalah-masalah dunia nyata melalui sebuah
karya sastra yaitu novel.
b) Tujuan Pembelajaran Sastra
Rusyana (1982: 7-8) mengemukakan bahwa tujuan
pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman tentang
sastra yaitu memperoleh pengalaman mengapresiasikan sastra, serta
memperoleh pengetahuan tentang sastra seperti sejarah sastra, teori
sastra dan kritik sastra.
Pembelajaran sastra diarahkan untuk memperbaiki budi pekerti
dan mempertajam kepekaan perasaan siswa. Belajar sastra adalah
belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan serta
lingkungan manusia di sekitarnya.
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, pembelajaran sasta di
SMA meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.
Standar kompetensi dalam pembelajaran sastra adalah memahami
berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan, kompetensi dasar
dalam pembelajaran sastra disesuaikan dengan silabus adalah
menganalisis unsur-unsur novel Indonesia/terjemahan, sedangkan
indikator pembelajaran sastra yaitu menganalisis unsur-unsur
ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, penokohan, dan latar).
31
c) Fungsi Pembelajaran Sastra
Menurut Rahmanto (1988: 16) pembelajaran sastra dapat
membantu pendidikan yang cakupannya meliputi 4 manfaat, antara
lain:
(1) Membantu Keterampilan Berbahasa
Membantu keterampilan berbahasa maksudnya adalah
pembelajaran sastra akan membantu siswa berlatih keterampilan
membaca, berbicara, menyimak, dan menulis yang masing-masing
erat hubungannya.
(2) Meningkatkan Pengetahuan Budaya
Meningkatkan pengetahuan budaya maksudnya adalah
sastra dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa ikut memiliki
kebudayaan yang disajikan melalui karya sastra tersebut.
(3) Mengembangkan Cipta dan Rasa
Mengembangkan cipta dan rasa maksudnya adalah bahwa
pembelajaran sastra dapat mengembangkan potensi siswa dan guru
hendaknya selalu menyadari bahwa setiap siswa memiliki
kepribadian dan kemampuan yang khas.
(4) Menunjang Pembentukan Watak
Menunjang pembentukan watak maksudnya adalah bahwa
pembelajaran sastra dapat membantu mengembangkan
pembentukan watak dan kualitas kepribadian siswa seperti
ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan baik itu segi
positif maupun negatif tergantung sastra yang dibaca.
32
d) Materi Pembelajaran Sastra
Guru hendaknya memilih materi atau bahan pembelajaran yang
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia, pembelajaran sastra di SMA meliputi standar kompetensi,
kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensi dalam
pembelajaran sastra adalah memahami berbagai hikayat, novel
Indonesia/novel terjemahan, kompetensi dasar dalam pembelajaran
sastra disesuaikan dengan silabus adalah menganalisis unsur-unsur
novel Indonesia/terjemahan, sedangkan indikator pembelajaran sastra
yaitu menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema,
penokohan, amanat, dan latar).
Pembelajaran apresiasi sastra di kelas XI SMA dapat
menggunakan novel. Novel yang digunakan sebagai materi harus
sesuai dengan perkembangan dan kemampuan siswa, mempunyai nilai
estetik dan mengandung nilai-nilai pendidikan yang berguna untuk
siswa. Karya sastra yang digunakan sebagai materi pembelajaran sastra
di kelas XI SMA adalah novel Sang Pencerah dengan penjelasan
mengenai struktur novel sebagai pijakan sebelum menganalisis nilai-
nilai religious dalam novel Sang Pencerah.
Menurut Rahmanto (1988: 27-31), untuk menentukan bahan
pembelajaran sastra yang tepat, harus mempertimbangkan beberapa
aspek yaitu: pertama dari sudut bahasa, kedua dari sudut psikologi, dan
ketiga dari sudut latar belakang.
33
1) Segi Bahasa
Penguasaan siswa terhadap bahasa sebenarnya mengalami
berbagai tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu,
dalam karya sastra mengalami perkembangan zaman yang meliputi
aspek kebahasaan.
2) Segi Psikologis
Pemilihan bahan pembelajaran sastra hendaknya juga
mempertimbangkan aspek psikologis siswa karena hal ini sangat
berpengaruh terhadap minat dan keengganan anak didik dalam
banyak hal. Perkembangan psikologis sangat berpengaruh terhadap
daya ingat, kemampuan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama,
dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem
yang dihadapi.
3) Segi Latar Belakang
Bahan pembelajaran dipilih berdasar latar belakang siswa. Hal
tersebut dimaksudkan agar masalah-masalah yang terdapat di
dalam karya sastra itu mendekati dengan apa yang dihadapi siswa
dalam kehidupan sehari-hari.
e) Metode Pembelajaran Sastra
Metode adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari
kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai jika tidak
menggunakan metode. Dalam mengajarkan suatu karya sastra (novel)
guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Berdasarkan
34
kebutuhan dan materi pembelajaran sastra, metode pembelajaran yang
masih menunjang untuk dipakai dalam pembelajaran sastra adalah
ceramah, diskusi, dan penugasan.
1. Metode Ceramah
Metode ceramah adalah penuturan informasi oleh guru
kepada siswanya secara lisan. Dalam metode ceramah ini murid
duduk, melihat dan mendengarkan serta percaya bahwa apa yang
diceramahkan guru itu adalah benar. Murid mengutip ikhtisar
ceramah semampu murid itu sendiri dan menghafalnya tanpa ada
penyelidikan lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan (Ismail,
2009: 19).
Kelebihan metode ceramah, yaitu
a. guru dapat memanfaatkan pengalaman-pengalamannya;
b. menjadikan siswa untuk menyimak dengan teliti dan kritis;
c. meningkatkan dan merangsang keinginan siswa untuk belajar.
Kelemahan metode ceramah yaitu:
a. mendorong siswa hanya untuk menghafalkan fakta-fakta saja;
b. siswa yang tidak terampil membuat catatannya akan tertinggal;
c. materi kurang terfokus karena terkadang pembicaraan sering
melantur.
Solusi kelemahan metode ceramah :
a. pada waktu berceramah, guru hendaknya mengulang poin-poin
yang penting untuk dicatat siswa.
35
b. Guru hendaknya tetap terfokus pada materi yang diajarkan dan
tidak terlalu melantur atau keluar dari konteks.
c. Ceramah dilakukan dengan waktu yang sesuai, tidak terlalu
lama dan tidak terlalu singkat.
2. Metode Diskusi
Metode diskusi merupakan suatu cara untuk menguasai
bahan pelajaran melalui tukar pendapat berdasarkan pengetahuan
dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecahkan suatu
masalah. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar
yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam proses
diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, dimana interaksi antara
dua atau lebih individu terlibat, saling tukar menukar pengalaman,
memecahkan masalah dan lain-lain (Ismail, 2009: 20).
Kelebihan metode diskusi, yaitu
a. Murid belajar bermusyawarah.
b. Murid mendapat kesempatan untuk menguji tingkat
pengetahuan masing-masing.
c. Belajar menghargai pendapat orang lain.
d. Mengembangkan cara bersikap ilmiah
Kelemahan metode diskusi:
a. Pendapat serta pertanyaan murid dapat menyimpang dari pokok
permasalahan.
36
b. Kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada
penyelesaiannya.
c. Membutuhkan waktu cukup banyak.
Solusi kelemahan metode diskusi :
a. Siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil,
kelompok ini terdiri dari siswa yang pandai dan kurang pandai,
pandai berbicara dan kurang pandai berbicara.
b. Guru mengusahakan penyesuaian waktu dengan berat topik
yang dijadikan pokok diskusi.
c. Sebaiknya guru jangan tergesa-gesa meminta respon siswa.
3. Metode Penugasan
Metode penugasan (resitasi) adalah metode penyajian bahan
dengan cara guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan
kegiatan belajar. Tugas yang diberikan dapat dikerjakan di kelas, di
rumah siswa, atau dimana saja asal tugas itu dapat dikerjakan
(Ismail, 2009: 21).
Kelebihan metode penugasan:
a. Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar
individual ataupun kelompok.
b. Dapat mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan.
c. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.
d. Dapat mengembangkan kreativitas siswa.
37
Kelemahan metode penugasan, yaitu:
a. Siswa sulit dikontrol apakah benar ia yang mengerjakan tugas
ataukah oranglain.
b. Khusus untuk tugas kelompok, jarang yang aktif
mengerjakannya dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu
saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan
baik.
c. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan
individu siswa.
d. Sering memberikan tugas yang monoton dapat menimbulkan
kebosanan siswa.
Solusi kelemahan metode penugasan :
a. Hendaknya penugasan dilakukan di dalam kelas agar guru lebih
mudah mengontrol siapa siswa yang benar-benar mengerjakan.
b. Hendaknya guru memberikan materi tugas yang perlu
diselesaikan oleh siswa dengan jelas.
c. Tujuan tugas yang diberikan akan lebih baik apabila dijelaskan
kepada siswa.
d. Apabila tugas kelompok, seyogyanya ada ketua dan anggota
kelompok sesuai dengan kebutuhan agar ada yang bertanggung
jawab.
e. Tempat dan lama waktu penyelesaian tugas hendaknya jelas.
38
f) Langkah-langkah Pembelajaran Sastra
Rahmanto (1988:43) mengatakan bahwa guru hendaknya selalu
memberikan variasi dalam menyampaikan pembelajaran sehingga
siswa tidak jenuh dan selalu siap dalam menanggapi berbagai
rangsangan.
Langkah-langkah pembelajaran menurut Rahmanto sebagai
berikut:
1) Pelacakan Pendahuluan
Guru mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan
untuk memperoleh pemahaman awal tentang novel yang akan
disajikan sebagai bahan ajar agar dapat menentukan aspek-aspek
yang perlu mendapat perhatian khusus dan masih perlu dijelaskan.
2) Penentuan Sikap Praktis
Penentuan sikap praktis yang menentukan informasi yang
dapat diberikan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam
memahami novel yang disajikan. Keterangan yang diberikan
hendaknya jelas dan seperlunya.
3) Introduksi
Pengantar yang diberikan tergantung pada setiap guru dan
keadaan siswa.
4) Penyajian
Tahap penyajian yaitu menyajikan materi yang telah
disiapkan untuk diajarkan kepada siswa. Guru sebaiknya
39
menggunakan cara yang bervariasi dalam materi agar dapat
disajikan lebih menarik sehingga siswa tidak merasa bosan.
5) Tugas-tugas praktis
Pada tahap ini, siswa diberi tugas-tugas pratis diawali dengan
pertanyaan-pertanyaan yang ringan.
g) Evaluasi
Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran,
dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil
belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar
dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Hamalik,
2011: 159).
Penilaian proses dan hasil sastra di SMA dapat berlangsung
melalui kegiatan baik lisan maupun tertulis. Evaluasi yang digunakan
dalam pembelajaran novel Sang Pencerah secara tertulis dengan
menggunakan tes atau esai. Evaluasi merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari keseluruhan proses belajar mengajar. Evaluasi
dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam
memahami dan mendalami materi yang dijelaskan peneliti.
Pembelajaran novel Sang Pencerah menggunakan bentuk tes esai. Tes
esai adalah sejenis tes belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat
pembahasan atau uraian kata-kata.
40
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi
adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mengalami
kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan pembelajaran.
Soal bentuk tes esai:
a. Jelaskan tema yang terdapat dalam novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral?
b. Jelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
41
BAB IIIMETODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang objek penelitian,
fokus penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, dan teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan
dalam penelitian.
A. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah nilai religius dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral yang diterbitkan oleh Mizan Pustaka
Jakarta, cetakan ketiga tahun 2010, tebal 461 halaman.
B. Fokus Penelitian
Penulis memfokuskan penelitian ini pada hubungan manusia dengan
Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan
alam sekitar dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral dan
skenario pembelajarannya di kelas XI SMA.
C. Sumber Data
Pada penelitian ini yang menjadi sumber data adalah novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral yang diterbitkan oleh Mizan Pustaka
Jakarta, cetakan ketiga tahun 2010.
41
42
D. Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2010: 203), instrumen penelitian adalah alat atau
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat
lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen dalam
penelitian ini adalah penulis selaku peneliti dengan alat bantu nota pencatat,
serta buku yang berkaitan dengan sastra.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik
observasi yaitu dengan cara membaca secara kritis dan teliti serta penuh
pemahaman pada novel Sang Pencerah. Penulis juga menggunakan teknik
catat untuk mencatat data-data penting yang ada di dalam novel sebagai data
dalam penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan teknik pustaka yaitu
menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah
sebagai berikut:
1. Membaca novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral secara kritis
dan teliti.
2. Mencatat data yang berupa narasi dan percakapan yang relevan dengan
nilai religius dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral.
3. Mengelompokkan data berdasarkan nilai religius dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral yang meliputi hubungan manusia
43
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam
sekitarnya.
F. Teknik Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jadi, metode yang
penulis gunakan yaitu dengan analisis isi (Syukur, 2009: 94). Teknik ini
membahas data dengan mengkaji teks novel untuk membedah dan
memaparkan nilai religius yang terkandung dalam karya novel tersebut,
sehingga dapat diketahui serta disimpulkan tentang isi kandungan nilai
religius dalam karya tersebut terutama pesan-pesan moral novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral.
Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral adalah sebagai berikut:
1. Menafsirkan data aspek-aspek religius yang meliputi hubungan manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam
sekitarnya, baik berupa narasi maupun percakapan secara pragmatis atau
semantis sesuai dengan sifat data tersebut.
Contoh penerapan teknik analisis isi secara pragmatis adalah sebagai
berikut:
“Idah, kalau Dahlan memang orang yang sangat hati-hati sepertikamu bilang, seharusnya dia tidak sampai melawan kiai Penghulusecara terbuka,” cecar Mas Noor” (SP, 2010: 238).
Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mas Noor
tidak sependapat dengan Idah jika Dahlan itu orang yang hati-hati
terbukti Dahlan melawan kiai Penghulu.
44
Contoh penerapan teknik analisis isi secara semantis adalah sebagai
berikut:
Setiap sore terdengar pengajian anak-anak putri dari arah serambiMasjid Gedhe, seperti tadi yang sempat kudengar (SP, 2010: 21).
Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap sore
Darwis mendengar anak-anak putri mengaji di serambi Masjid Gedhe.
2. Menganalisis data dari segi pembelajaran sesuai atau tidak sebagai bahan
ajar dan langkah-langkah pembelajaran novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral di SMA.
3. Menyimpulkan data hasil penelitian.
G. Teknik Penyajian Hasil Analisis
Teknik yang digunakan untuk penyajian hasil analisis adalah
menggunakan metode informal. Metode informal adalah penyajian hasil
analisis data dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993:145). Dengan
demikian penulis menyajikan hasil analisis aspek religius dalam novel Sang
Pencerah yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan
manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya dipaparkan dengan kata-kata
biasa tanpa menggunakan tanda dan lambang.
45
BAB IVPENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA
Pada bab ini dibahas dua hasil pelaksanaan penelitian yaitu penyajian data
dan pembahasan data hasil penelitian.
A. Penyajian Data
Untuk membahas data hasil penelitian, terlebih dahulu penulis
menyajikan data-data hasil penelitian supaya dapat dibahas secara benar dan
teliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa narasi dan percakapan
yang relevan dengan nilai-nilai religius dalam novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian
adalah novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
1. Tabel Struktur Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral
No Unsur pembentuk karya sastra Penyajian Data
1 Tema 83, 84, 110, 111, 241, 245, 360,368, 294, 399, 426, 442, 443.
2 Tokoh dan penokohan 294, 6, 82, 45, 67, 74, 78, 79, 150,93, 238, 128, 182, 129, 140, 178,222, 263, 303, 312, 314, 413.
3 Alura. Awal
1. Paparan 62. Rangsangan 71
3. Gawatan 206b. Tengah
1. Tikaian 842. Rumitan 204, 206, 2113. Klimaks 244, 245
c. Akhir1. Leraian 260, 2622. Selesaian 417, 424.
45
46
4. Latara. Latar tempat 141, 143, 267, 239, 402, 403,b. Latar waktu 125, 254, 100, 96, 21, 101, 160,
137, 254, 164, 450, 11, 160, 161.c. Latar social 174, 175, 46, 93, 190, 129, 441,
93.5. Amanat 90, 229, 391, 81, 263.
2. Tabel Nilai Religius yang ada dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal
Nasery Basral
No Nilai-Nilai Religius Penyajian Data
1. Hubungan Manusia dengan
Tuhan
212,161, 91, 46, 7-8, 175
2. Hubungan Manusia dengan
Manusia
11, 14, 24, 49, 63, 65, 156.
3. Hubungan Manusia dengan
Alam
90
3. Skenario Pembelajaran Novel Sang Pencerah di kelas XI SMA
Pembelajaran novel di sekolah, khususnya SMA dapat dikatakan
sama dengan jenis sastra prosa lainnya. Pembelajaran sastra atau novel
berkaitan dengan strategi pembelajaran. Di bawah ini adalah pembelajaran
novel tersebut.
a. Tujuan Pembelajaran
Kurikulum tingkat satuan pendidikan menggunakan kemampuan
dasar dan indikator hasil belajar sebagai ganti tujuan pembelajaran
umum dan khusus.
47
b. Bahan / Materi Pembelajaran
Bahan pembelajaran merupakan suatu yang diajarkan dalam
kegiatan pembelajaran. Bahan pembelajaran disesuaikan dengan
kurikulum. Dalam pemilihan bahan pembelajaran juga harus
memperhatikan sudut bahasa, latar belakang kebudayaan, dan
psikologi.
c. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran adalah cara yang dipakai dalam kegiatan
pembelajaran. Metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan
tujuan, keadaan siswa, dan suasana kelas. Metode pembelajaran yang
digunakan dalam pembelajaran siswa di kelas XI adalah metode
ceramah, diskusi, dan penugasan.
d. Strategi Pembelajaran
Strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar adalah
strategi sastra yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) tahap
penjelajahan, (2) tahap interpretasi, dan (3) tahap rekreasi.
e. Langkah-Langkah Pembelajaran
Langkah-langkah pembelajaran merupakan tahap yang
dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut
dipilih dan ditentukan oleh masing-masing guru sesuai dengan metode
yang digunakan. Langkah-langkah pembelajaran di kelas XI SMA
meliputi pelacakan pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi,
penyajian, diskusi dan pengukuhan.
48
f. Sumber Belajar
Sumber belajar merupakan buku pelajaran yang diwajibkan,
buku yang sesuai, buku pelengkap, pengalaman, dan minat siswa.
g. Waktu Pembelajaran Sastra
Waktu yang disediakan untuk pembelajaran sastra dapat diatur
dengan keleluasaan dan kedalaman materi.
h. Evaluasi
Evaluasi identik dengan penilaian. Evaluasi dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan materi siswa terhadap
materi yang dibahas.
B. Pembahasan Data
1. Struktur Novel Sang Pencerah
a. Tema
Masalah merupakan suatu unsur untuk membangun tema
sehingga timbul beberapa masalah yang mendukung tema. Masalah
yang terdapat pada novel Sang Pencerah antara lain :
1) Masalah Perbedaan Pendapat
Dalam sebuah diskusi, perbedaan pendapat dari peserta
diskusi itu wajar dan sering terjadi, begitu pun pada Darwis yang
berbeda pendapat dengan kakak iparnya saat membicarakan tradisi
nyadran yang akan dilaksanakan di zaman Kala Bendu.
"Maaf, Kiai. Mengingat kondisi masyarakat kita yangsedang prihatin di zaman Kala Bendu ini, apakah tidaksebaiknya acara Nyadran dibuat sederhana saja?” tanyaku.
49
Beberapa jamaah langsung berbisik-bisik. Beberapa pasangmata lainnya di tempat ini memandangku dengan sorot mataaneh. Kiai Penghulu Kamaludiningrat malah menyipitanmatanya, seperti ingin memastikan bahwa dia tidak salahlihat sang penanya adalah anak dari Kiai Abu Bakar yangmerupakan imam dan khatib Masjid Gedhe Kauman.Melihat acaranya menatap seperti itu, aku duga KiaiKamaludiningrat akan menjawab dengan nada keras”. (SangPencerah: 2010 :83).
Perdebatan Kiai Noor dengan Darwis berlanjut di rumah.
Kiai Noor berbicara dengan suara yang tegas kepada Darwis jika
upacara nyadran hanya diisi dengan bacaan doa-doa maka orang-
orang tidak akan datang ke Masjid Gedhe.
"Dan kini perdebatan di antara anggota keluargaku benar-benar terjadi setelah Mas Noor juga ikut angkat bicara.“Kalo untuk soal sedekah itu tidak usah khawatir, Wis.Masjid Gedhe selalu melakukan pemberian sedekah setiaphari Jumat sehingga umat Islam mendadak jadi banyakterlihat pada hari itu." Nada suara Mas Noor tegas sepertibiasa. "Kalau nyadran ini isinya hanya membaca doa-doasaja, dan tidak ada orang yang mau datang berdoa, lantassiapa yang mau bertanggung jawab? Dan bagaimana kitamenjelaskannya kepada Ngarsa Dalem?” (Sang Pencerah,2010 “ 84).
2) Masalah Perjodohan
Pada zaman dahulu perjodohan sering dilakukan apalagi
dalam masyarakat Jawa, seperti halnya orang tua Walidah yang
menjodohkan Walidah dengan Darwis.
"Bapak dan Ibu sudah perhatikan selama ini, Darwis adalahcalon suami yang sangat tepat untukmu. Pengetahuanagamanya bagus, Bahasa Arabnya lancar, pintar,perilakunya juga alim tidak seperti orang-orang didikanBelanda yang pintar tapi melupakan agama, dan yang takkalah penting, keluarganya juga sangat alim dan dihormatimasyarakat. Bapak yakin dunia akhirat bahwa Darwis akanbisa membawa kehidupan keluarga kalian nanti menjadi
50
keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah, dia akanmenjadi imam yang baik bagimu, pelindung yangbertanggung jawab, dan membimbingmu sebagi muslimahyang akan lebih salihah dalam menjalani hidup.” (SangPencerah, 2010 : 110)
Dalam kutipan di atas terlihat bahwa K.H. Muhammad
Fadil sangat ingin menjodohkan Walidah dengan Darwis karena
beliau yakin jika menikah dengan Darwis kehidupan keluarga
Walidah akan bahagia karena Darwis adalah sosok calon imam
yang baik.
"Alhamdulillah. Kalau begitu Bapak tinggal membicarakanhal ini dengan Kiai Abu Bakar supaya semua persiapanpernikahan bisa berjalan berjalan lancar. Semoga Allahridha dengan pilihan ini, Idah.”(Sang Pencerah, 2010 : 111)
3) Masalah Kerusuhan/Pengrusakan
Setelah Kiai Dahlan diperingatkan oleh marbut Masjid
Gedhe agar menutup langgarnya, namun beliau tetap tidak akan
menutup langgar kidul dan akhirnya langgar kidul dihancurkan
oleh rombongan kuli suruhan Kiai Kamaludiningrat. Saat itu Kyai
Dahlan yang sedang berada di rumah langsung bergegas menuju
Langgar kidul karena mendengar suara tahlil yang keras.
“Lamat-lamat kudengar suara tadarus para santri ituberubah menjadi suara tahlil yang semakin keras danberirama."Laa ilaaha illallah, laailaah illallah, laa ilaahaillallah . . . " Dan jarak suara itu terdengar semakin dekat.Aku tersentak, ini sudah bukan suara tadarus lagi yangkudengar dalam bayangan, melainan suara sekumpulanorang yang sedang berjalan di luar, membelah kegelapanmalam.” “Laa ilaaha illalahh . . . .”(Sang Pencerah, 2010 :241).
51
Orang-orang suruhan Kyai Kamaludin langsung
mengayunkan alat yang berada di tangan mereka masing-masing
untuk menghancurkan Langgar Kidul.
"Orang-orang itu pun langsung mengayunkan linggis,cangkul, martil dan apa pun peralatan yang mereka bawa kedinding langgar kidul. Benturan benda padat yang bertalu-talu di tengah malam itu menimbulkan efek magis anehyang belum pernah didengar warga sebelumnya. Serpihankayu yang pecah akibat dilinggis mulai beterbangan. Satupersatu bagian tembok runtuh, menimbulkan luka yangsemakin besar di hati para santri. Daniel, Hisyam, Sangidudan para santri lain mulai menangis, kecuali Jazuli yangmelihat dengan tatapan benci tapi tak bisa berbuat apa-apakarena para pekerja itu dikawal oleh beberapa orang polisiBelanda.”(Sang Pencerah, 2010 : 245).
4) Masalah Fitnah
Dalam kehidupannya, Kiai Dahlan secara terang-terangan
dituduh sebagai Kiai Kafir oleh warga dan orang-orang yang tidak
menyukai Kiai Dahlan.
"Iya, Mas." kata Sangidu sambil mengangguk-anggukkankepalanya. Beberapa langkah kemudian terdengar teriakan-teriakan mengejek dari sejumlah orang di belakang kami."Lihat itu Kiai kafir! Kiai kafir! Kiai kafir!” ujar merekasambil memukul rebana sehingga teriakan itu terdengarseperti sebuah tembang." (Sang Pencerah, 2010 : 360)
Ibu Hisyam mengatakan kepada Sudja untuk apa dia
mengaji kepada kiai yang perilaku kesehariannya menyerupai
orang kafir.
"Nak Sudja, ndak perlu pinter-pinter amat ngaji buat tahubahwa kalau ada orang sehari-harinya menyerupai orangkafir, berpakain seperti orang kafir, dan hidup dengan caraorang kafir, maka orang itu adalah bagian dari orang-orangkafir.” (Sang Pencerah, 2010 : 368).
52
Saat itu kiai Dahlan kedatangan tamu seorang kiai dari
Magelang yang juga secara tidak langsung menunjuk kepada Kiai
Dahlan bahwa apa yang dikatakan orang-orang tentang Kiai
Dahlan yang menyebutnya kiai kafir adalah benar.
"Kalau memang Kiai tahu arti nama itu, kenapa Kiaimenggunakan perlengkapan kafir dalam menjalankansekolah ini?” suaranya dalam nada tinggi. "Baru sekali inisaya melihat ada madrasah yang dibikin seperti sekolahorang-orang kafir!” (Sang Pencerah, 2010 : 394).
5) Masalah Sosial
Kiai Dahlan adalah orang yang mempunyai jiwa sosial yang
tinggi. Hal ini terlihat saat beliau membagi-bagikan makanan dan
pakaian kepada orang miskin di sekitar Alun-Alun Utara dan juga
membuka pengobatan di rumahnya.
"Keesokan harinya aku mengunjungi Alun-Alun Utaraditemani Siraj, Fakhrudin, Hisyam, Sudja, dan Dirjo untukmembagi-bagikan makanan dan pakaian kepada orangmiskin. Sudja melihat seorang anak kecil pengemis yangsedang sakit dan tidur melingkar.”"Ini ada pakaian dan makanan, buat ibu dan anak ibu. Kalaubisa nanti sore datang ke Kauman, langgar kidul. Saya akankasih obat.” (Sang Pencerah, 2010:399).
6) Masalah Kesalahpahaman
Kesalahpahaman terjadi pada saat surat perizinan
perkumpulan Muhammadiyah sampai di tangan Kiai Penghulu.
Pada saat itu Kiai Penghulu menolak perizinan pendirian
Muhammadiyah dengan alasan Kiai Dahlan akan menggeser
kedudukan Kiai Penghulu sebagai residen.
53
"Baiklah saya bacakan isinya," ujar Kiai Penghulu sambilmembuka isi surat dan membacanya keras-keras. Ketikasampai pada bagian tempat namaku tertulis, Kiai Penghulumembaca lebih keras lagi. Katanya,"Di sini tertulis bahwaKiai Ahmad Dahlan akan menjadi resident," Kiai Penghuluberhenti sejenak membaca dan memperhatikan kalimat itu,"Benar, memang di sini tertulis residen." ujar Kiai Penghulusambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan.Nafas Kiai Penghulu langsung naik turun dengan cepat,wajahnya memerah, suaranya bergetar karena amarah.”(Sang Pencerah, 2010 :426).
Kiai Penghulu berkata kepada Rykbestur seandainya Kiai
Dahlan menjadi seorang Resident beliau akan membahayakan
posisi Kiai Penghulu yang selama ini menjadi Kiai Penghulu
Masjid Gedhe.
"Begini, Pak Rykbestuur,” ujar Kiai Penghulu.” KiaiDahlan itu pernah diangkat Sri Sultan sebagai Khatib AminMasjid Gedhe Kauman. Lalu, atas keinginan sendirimengundurkan diri beberapa tahun lalu. Sekarang dia inginmenjadi Resident Muhammadiyah, berarti Kiai Dahlantidak hanya ingin menguasai umat Islam Muhammadiyah,tapi juga umat Islam Kauman dan semua yang bermukim diKaresidenan Yogyakarta. Lalu, bagaimana jika nanti orang-orang Kauman tidak mau menuruti saya lagi sebagai HoofdPenghulu, sebagai Kiai Penghulu Masjid Gedhe? Ini bukanhanya berbahaya bagi umat Islam, tapi juga bagi KesultananNgayogyakarta Hadiningrat,” (Sang pencerah, 2010 : 442).
Menentukan tema pokok sebuah cerita pada hakikatnya
merupakan proses penggabungan masalah dan menilai masalah
yang terdapat dalam novel. Kiai Dahlan merupakan tokoh utama
yang sering memunculkan konflik dengan tokoh lain. Di antaranya
masalah perbedaan pendapat, perjodohan, perusakan/ kerusuhan,
sosial, dan kesalahpahaman.
54
Berdasarkan paparan peristiwa di atas, dapat disimpulkan
bahwa tema dalam novel Sang Pencerah adalah perjuangan Kiai
Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam dari unsur bidah dan
perjuangan mendirikan Muhammadiyah.
b. Tokoh dan Penokohan
1) Tokoh
Jenis tokoh yang terdapat dalam novel Sang Pencerah yaitu
sebagai berikut:
a) Tokoh utama dan tokoh tambahan
Tokoh utama novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery
Basral adalah K.H. Ahmad Dahlan karena tokoh K.H. Ahmad
Dahlan muncul di setiap cerita, kemunculannya memegang
peranan yang penting dan mempengaruhi alur cerita, juga
berhubungan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sosok Kiai Ahmad
Dahlan sebagai tokoh utama cerita disebutkan dalam setiap
episode cerita.
Tokoh tambahan dalam novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral lebih banyak dibandingkan dengan tokoh
utama. Beberapa di antaranya adalah Sri Sultan
Hamengkubuwono VII, Kiai Penghulu Kamaludiningrat, Kiai
Haji Abu Bakar, Pono, Kiai Hamid, Kiai Haji Muhammad
Saleh, Kiai Noor, Nyai Walidah (Isteri Kiai Ahmad Dahlan),
55
Kiai Sholeh Darat, Syaikh Ahmad Al-Minangkabawi, Kiai
Fadlil, Danil dan Jazuli, Dr. wahidin, Sudja, Joyosumarto.
b) Tokoh protagonis dan tokoh antagonis
Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi oleh
pembaca. Dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery
Basral tokoh protagonis di antaranya Sri Sultan
Hamengkubuwono VII, Nyai Walidah, Kiai Shaleh dan Nyai
Shaleh, Sudja, Sangidu, Hisyam, Kiai Abu Bakar, dan Kiai
Ibrahim, Kiai Sholeh Darat, Kiai Fadlil, Danil dan Jazuli, dan
dokter. Wahidin. Mereka sangat membantu dan mendukung apa
yang dicita-citakan tokoh utama yaitu K.H. Ahmad Dahlan.
Tokoh antagonis dalam novel Sang Pencerah
diantaranya Kiai Penghulu Kamaludiningrat, Kiai Noor dan
Nyai Noor, Kiai Muhsin karena mereka sering beroposisi
dengan Kiai Ahmad Dahlan.
2) Penokohan
a) Kiai Ahmad Dahlan (Darwis)
Secara analitik sosok Kiai Ahmad Dahlan (nama kecil
Muhammad Darwis) digambarkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan
adalah anak dari Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Abu bakar
merupakan keturunan ke-10 dari Syaikh Maulana Malik
Ibrahim, salah satu tokoh pembawa Islam di Tanah Jawa.
“Bapakku bukan cuma memiliki pengetahuan yangmendalam tentang agama Islam, tapi juga memiliki
56
wibawa khusus sebagai tokoh agama karena dia adalahketurunan ke-10 dari Syaikh Maulana Malik Ibrahim,penyebar agama Islam di Gresik pada abad ke-15,”
Sosok Kiai Abu Bakar dalam mendidik Kiai Ahmad
Dahlan sangat penting. Bapaknya merupakan salah tokoh yang
berpengaruh di Yogyakarta. Di dalam novel Sang Pencerah ini,
ia digambarkan sebagai pendiri organisasi kemasyarakatan
Muhammadiyah. Dikisahkan bahwa proses pendirian organisasi
Muhammadiyah tidaklah berjalan mulus, tetapi mendapatkan
penentangan dari berbagai kalangan, terutama dari kiai-kiai
seniornya hingga masyarakat di sekelilingnya. Namun
dukungan kuat dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII
memudahkan pendirian organisasi tersebut.
Penentangan terhadap langkah-langkah dakwah yang
dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan misalnya tergambar dari
kutipan di bawah ini:
“Terima kasih, Sinuwun. Tapi pemikiran sayatampaknya tidak dibutuhkan di Kauman, terlalu banyakyang tidak setuju dibandingkan dengan yang sepakat.”(Sang Pencerah, 2010:293)
Dari kutipan di atas digambarkan secara dramatik
rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh Kiai Dahlan di
dalam menjalankan dakwah pembaruannya di Kauman.
Berbeda dengan masyarakat Kauman pada umumnya, Sri
Sultan Hamengkubuwono mendukung pemikiran-pemikiran
Kiai Ahmad Dahlan.
57
b) Sri Sultan Hamengkubuwono VII
Dalam novel Sang Pencerah ini tokoh Sri Sultan
Hamengkubuwono VII memiliki peran besar dalam membantu
tokoh utama (Kiai Ahmad Dahlan) dalam mewujudkan cita-
citanya untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Sejak
awal, Sri Sultan Hamengkubuwono VII sebagai pemimpin
Keraton Yogyakarta mendukung pemikiran dan perjuangan
Kiai Ahmad Dahlan.
Peran Sri Sultan Hamengkubuwono dalam mendukung
perjuangan Kiai Ahmad Dahlan misalnya ditunjukkan dalam
kutipan di bawah ini:
“Pergilah berhaji lagi Kiai Dahlan. Keraton yang akanmembiayai. Perdalam lagi ilmu agama sekaligusmenjalin hubungan dengan para ulama pembaru dariMesir, Syiria, Madinah, dan tempat-tempat lain. Sayadengan Kiai berhubungan cukup dekat dengan paraSyaikh dari kalangan pembaru seperti Syaikh JamaluddinAl-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh?” (SangPencerah, 2010: 4)
Dari kutipan di atas jelas terlihat secara dramatik bahwa
Sri Sultan Hamengkubuwono VII mendukung terhadap
perjuangan Kiai Dahlan cukup berarti. Hal tersebut juga
menyentuh secara emosi terhadap diri Kiai Dahlan.
c) Kiai Penghulu Khalil Kamaludiningrat
Kiai Penghulu Kamaludiningrat merupakan salah satu
dari Kiai yang cukup berpengaruh di jajaran kiai-kiai di
58
Kesultanan Yogyakarta. Kiai Penghulu Kamaludiningrat
dikenal tegas dalam membimbing santri-santrinya. Kiai
Penghulu Kamaludiningrat memiliki sejumlah santri di masjid
Gedhe Kauman. Kegiatan mengajar telah menjadi rutinitasnya
setiap hari. Suara anak perempuan yang mengaji pada Kiai
Penghulu harus tetap keras dan jelas karena beliau sangat peka
terhadap bacaan Alquran. Kiai Penghulu secara analitik
digambarkan seperti pada kutipan berikut:
“Suara mereka tak bisa melunak meski hanya untukseperseratus detik karena telinga Kiai Haji PenghuluKholil Kamaludiningrat yang memimpin pengajian itusangat peka.” (Sang Pencerah, 2010:6)
Memimpin pengajian telah menjadi rutinitas bagi Kiai
Kamaludiningrat. Ia tidak segan-segan memarahi santri yang
main-main ketika membaca ayat-ayat Alquran. Sosoknya yang
tegas ditakuti oleh para santri, baik laki-laki maupun
perempuan.
Kiai Penghulu juga memegang peranan penting di
dalam kepemimpinan Masjid Gedhe Kauman. Ia bertanggung
jawab terhadap operasional masjid secara keseluruhan. Ia juga
memimpin ketika diadakan rapat-rapat mengenai kebijakan
penting menyangkut masjid, seperti kutipan berikut:
“Rapat bulanan pengurus Masjid Gedhe berlangsung diserambi masjid dan dipimpin langsung oleh KiaiPenghulu Kamuludiningrat. Sepanjang pengalamankumengikuti rapat-rapat takmir di sini, inilah rapat yang
59
cukup besar dari segi jumlah beserta.” (Sang Pencerah,2010:82).
d) PonoPono merupakan teman Darwis. Semasa kecil hampir
setiap hari Darwis dan Pono bersama-sama dalam mencari ilmu
dan mencari guru baru. Pono menjadi teman diskusi sekaligus
mencurahkan kegelisahan Darwis tentang perilaku masyarakat
yang ia anggap janggal dan bertentangan dengan Islam, seperti
kutipan berikut ini:
“Aku mau meneruskan kerja bapakku saja, No (Pono).Aku suka bingung melihat warga yang pada salat danmengaji tapi rajin sesajen di kuburan.” (Sang Pencerah,2010:45).
Pono dan Darwis tidak bisa berbuat banyak dalam
mengubah perilaku masyarakat yang demikian. Bahkan untuk
biaya hidupnya ia bergantung pada pinjaman yang berbau riba.
Ibu Pono sering meminjam uang kepada rentenir, seperti
digambarkan Pono berikut ini:
“Wajah riang Pono langsung berubah sedih. “Iya Wis,ibuku pinjam uang dari Mak Odah. Nantimengembalikannya harus lebih banyak dari jumlahpinjaman.” (Sang Pencerah, 2010:45).
Pertemanan Pono dengan Darwis berlanjut hingga
Darwis memutuskan untuk menuntut ilmu ke Makkah yang
mengantarkan Darwis menjadi pemuda yang kokoh dalam
pendiriannya.
60
e) Kiai Abdul Hamid
Secara dramatik Kiai Hamid digambarkan bahwa ia
merupakan salah satu guru dari Kiai Dahlan. Sebagai guru,
pemikiran-pemikirannya juga turut mempengaruhi pemikiran
Kiai Dahlan.
“Kiai Abdul Hamid mengambil kitab fiqih di depanku.Dia mengangkatnya dna mengayunkannya perlahan-lahan. “seluruh isi kitab ini, ya seluruh isi kitab ini, jikakita pelajari dan hayati secara benar, maknanya cumasatu yang baru saja kamu perhatikan itu, Darwis.Menyantuni anak yatim.” (Sang Pencerah, 2010:67).
f) Kiai Haji Muhammad Saleh dan Nyai Shaleh
Kiai Haji Muhammad Saleh merupakan sosok yang
alim. Selain sebagai keluarga (kakak ipar Kiai Dahlan), ia juga
menjadi guru yang menguasai Bahasa Arab. Secara analitik
penokohan Kiai Haji Muhammad Saleh terlihat pada kutipan
berikut
“Setelah acara ruwatan selesai, aku pergi ke rumahkakak iparku Kiai Haji Muhammad Saleh untuk belajarbahasa Arab. Menurut Bapak, kakak iparku itu adalahsalah seorang kiai yang bahasa Arabnya sangat baikbukan hanya di Kauman, tapi juga di seluruhKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.” (SangPencerah, 2010:74).
Kiai Shaleh dan Nyai Shaleh juga berperan dalam
mengembalikan moral Kiai Dahlan dalam mengajar dan
berdakwah. Ketika Kiai Dahlan memutuskan untuk pindah ke
Semarang, Kiai Shaleh datang dan menjanjikan untuk
membantu jalan dakwah dengan cara membantu membangun
61
kembali Langgar Kiai Dahlan yang terlihat secara dramatik
dalam kutipan di bawah ini:
“Langgarmu bisa dibangun lagi Dahlan. Nanti Kangmasyang bangun,” (Sang Pencerah, 2010:74).
g) Kiai Noor
Kiai Noor merupakan satu dari beberapa Kiai yang ada
di Kesultanan Ngayogyakarta yang juga disegani. Sikapnya
yang tegas terkadang membuat Ahmad Dahlan terpokok ketika
bercengkrama dengannya. Kiai Noor juga mengajar beberapa
disiplin ilmu, termasuk Darwis pernah menimba ilmu
kepadanya.
“Pada suatu hari, aku mengikuti pengajian Mas Noorbersama empat orang santri muda lainnya. Dari limaorang murid Mas ini, aku paling bersih meski warnakulitku sendiri sawo matang” (Sang Pencerah, 2010:78).
Kiai Noor memiliki pandangan yang cukup berbeda
dengan para kiai lainnya dalam menyikapi perbedaan terutama
dalam menyangkut perbedaan pemikiran yang berasal dari
orang Barat. Pandangan tersebut juga terlihat dari cara
menyikapi hal-hal yang berbau orang Barat, misalnya terlihat
dalam kutipan berikut:
“Siapa yang bisa melawan Belanda?” jawab Mas Noor.“Para panglima perang Pangeran Diponegoro yangsemanya ulama saja akhirnya pada bubar, dibuat terceraiberai…” (Sang Pencerah, 2010:79).
Pandangan kerasnya terhadap pemikiran yang
berpengaruh juga ditunjukkan dalam penggambaran sosok Kiai
62
Noor oleh Kiai Ahmad Dahlan yang secara analitik terlihat
dalam kutipan berikut:
“Kedua kiai ini memang memiliki sikap tegas, dan seringbicara terus terang tanpa banyak basa basi. Namunketegasan Mas Noor kurasakan lebih sering diarahkantentang bagaimana umat Islam harus menghadapi kaumBarat. Jika menyangkut keadaan di dunia Muslimsendiri, Mas Noor terasa lebih waspada terhadap padapemikir muda Islam yang menginginkan perubahandalam cara berfikir umat” (Sang Pencerah, 2010:150).
h) Nyai Walidah
Nyai Walidah adalah istri dari Kiai Ahmad Dahlan.
Hidupnya diabdikan untuk menemani hari-hari suaminya dalam
menjalankan dakwah, sejak merintis hingga berhasil
membentuk organisasi besar yaitu Muhammadiyah.
“Namaku Siti Walidah binti Muhammad Fadlil. Ya,orangtuaku adalah Kiai Haji Muhammad fadlil, kiai yangjuga dikenal sebagai pedagang kain batik. Ibukudipanggil orang-orang Nyai Fadlil” (Sang Pencerah,2010:93).
Secara dramatik Walidah digambarkan sebagai sosok
yang setia dan penyabar dalam menghadapi penentangan
masyarakat terhadap langkah-langkah dakwah suaminya. Ia
juga sosok perempuan yang cerdas dalam memberikan
pertimbangan-pertimbangan suaminya dalam mengambil
keputusan tertentu. Bahkan ketika menghadapi kakaknya
sendiri Kiai Noor ketika menuduh Kiai Dahlan melenceng jauh
dari ajaran Islam. Menurut Walidah.
63
“Saya percaya Mas Dahlan punya alasan yang sangatkuat atas segala perbuatan dan ucapannya. Dia orangyang sangat hati-hati. Kita sudah tahu bagaimana MasDahlan sejak kecil. Behkan sebelum aku lahir, Mas Noorsudah lebih dulu tahu dan mengenali baik MasDahlan…” (Sang Pencerah, 2010:238).
i) Kiai Sholeh Darat
Kiai Sholeh Darat adalah salah satu kiai yang alim.
Karyanya telah mempengaruhi sebagian ulama Indonesia yang
pernah belajar dengannya. Kiai Sholeh Darat juga dikenal
sebagai seorang penulis. Beberapa hasil karyanya adalah kitab
Faid Ar-Rahman, Majmu’ah As-Syariah al-Kafiyah li Al-
Awam. Secara analitik, penggambaran tokoh Kiai sholeh Darat
terlihat dalam kutipan berikut:
“…beliau adalah seorang penulis produktif. Selainmenulis kitab Faid Ar-Rahman, Kiai menulis sejumlahkarya lain seperti Majmu’ah As-Syariah al-Kafiyah li Al-Awam…” (Sang Pencerah, 2010:129).
j) Daniel dan Jazuli
Daniel dan Jazuli adalah dua saudara kakak beradik
yang diterima sebagai santri oleh Kiai Dahlan setelah mengisi
khotbah di Masjid Gedhe. Kedua kakak beradik bersaudara ini
memutuskan untuk menjadi santri Kiai Dahlan karena di tempat
nyantri lamanya ia merasa tidak senang, dan akhirnya keluar. Ia
memutuskan untuk menimba ilmu di Langgar Kidul milik Kiai
Dahlan.
“Kedua kakak beradik itu bertatapan dengan ekspresipuas. “Terima kasih Kiai, “Tutur Daniel sambil
64
mencium tanganku, diikuti adiknya Jazuli melakukanhal yang sama. Aku mengangguh. “jangan lupa ajakteman-teman kalian yang lain.” (Sang Pencerah,2010:178).
Penggambaran watak tokoh Jazuli secara dramatik
tampak jelas bahwa ia merupakan anak yang suka bertanya
tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, bahkan ia tidak
segan-segan mempertanyakan agama, seperti ketika bertanya
kepada Kiai Dahlan.
“Yang disebut agama itu sebenarnya apa?”, TanyaJazuli tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaan ini tidaklazim ditanyakan dan tidak akan dijawab oleh kiaitradisional. “Sekarang aku mengerti, mengapa Jazulitidak betah di Pesantren lamanya. Jika dia menyakanhal-hal seperti ini kepada para guru agama dan kiai yangkolot, jawaban yang akan dia terima hanyalah deretankemarahan dari sang guru” (Sang Pencerah, 2010: 182).
k) Dirjo
Secara analitik watak Dirjo digambarkan bahwa ia
adalah anak yang berani dalam mengambil tindakan yang
dianggapnya benar. Dirjolah sosok yang berani membuat
goresan penanda saf di masjid Gedhe Kauman yang membuat
marah Kiai Penghulu.
“Tiba-tiba terdengar suara keras. “saya yang melakukanPakde!” aku melihat kea rah datangnya suara. Dirjo!Keponakan Kiai Penghulu itu mengangkat tangannyatinggi-tinggi. “aku yang meminta kawan-kawanku untukmembuat saf baru itu” (Sang Pencerah, 2010:222).
65
l) Kiai Ibrahim
Sosok Kiai Ibrahim adalah kiai sepuh mantan Kiai
Penghulu di Masjid Gedhe yang saat ini ditempati oleh Kiai
Penghulu Kamaludiningrat. Ia digambarkan sebagai
pengangkat modal Kiai Dahlan setelah peristiwa pembakaran
Langgar Kidul. Ia membantu pendirian kembali Langgar Kidul
dengan membantu materi yaitu uang.
“Ini juga uangku untukmu Dahlan,” sambung KiaiIbrahim tiba-tiba. “Jumlahnya tidak banyak tapi untukmenenangkanmu bahwa keluarga selalu mendukungmu”(Sang Pencerah, 2010:263).
m) Dokter Wahidin Sudirohusodo
Dokter Wahidin adalah seorang dokter yang memiliki
pandangan luas dan pintar. Ia resah dengan kondisi masyarakat
Jawa, kemudian ia memutuskan untuk membuat majalah
Retnadoemilah yang dicetak dalam bahasa Jawa dan Melayu
(Sang Pencerah, 2010:303).
c. Alur
Menurut Sudjiman (1988: 30), struktur alur dapat dibagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1) Awal
Awal alur cerita dimulai dari paparan (exposition),
rangsangan (inciting moment), yang merupakan bagian alur yang
mengarah pada terjadinya tindakan awal sang tokoh. Kemudian,
66
alur cerita dilanjutkan dengan gawatan (rising action), yang
merupakan bagian dari alur yang menunjukkan gerak menanjak
masalah.
(a) Paparan (exposition)
Tahap paparan diceritakan kehidupan masyarakat
Kauman yang hampir setiap harinya mempunyai aktivitas
yang sama. Setiap harinya anak-anak perempuan mengaji,
sedangkan anak laki-laki asik bermain bola.
“Waktu bergerak ajek di Kauman, dengan pola yangsama dari hari ke hari, dengan perincian peristiwahampir serupa dari waktu ke waktu. Seperti saat inimisalnya, ketika suara anak-anak perempuan yangmembaca kitab suci Alquran datang dari satu sisi,sedangkan sorak tawa, teriak girang, kadang-kadangbercampur makian kemarahan spontan anak-anaklelaki datang dari sisi lain” (Sang Pencerah, 2010: 6).
(b) Rangsangan (inciting moment)
Tahap rangsangan digambarkan pada permasalahan-
permasalahan yang terjadi pada Darwis. Pada tahap ini dimulai
ketika Darwis mendapati tradisi yang dianggapnya menyalahi
ketentuan-ketentuan agama.
Darwis (nama kecil Kiai Dahlan) adalah anak tokoh
besar Kiai Abu Bakar yang dikenal alim di antara para kiai di
Kasultanan Yogyakarta. Darwis kecil dihadapkan pada
realitas masyarat tradisional di sisi yang satu dan realitas
penjajahan di sisi yang lain. Sebagai masyarakat yang
bercorak tradisional, banyak perilaku masyarakat seperti
67
yasinan untuk orang meninggal, sesajen, nyadran dan
ruwatan, dan praktik riba yang digugat dan turut menjadi
tanya di kepala Darwis.
“Dalam perjalanan pulang, pertanyaan soal ruwatan dikepalaku bukannya padam, malahan makin berkobar.Mengapa ruwatan ini begini perlu? Kalaupunmemang sangat perlu, apakah harga-harga barangyang mahal dan memberatkan masyarakat sepertidisebutkan anggota takmir muda itu tidak bisadijadikan pertimbangan dalam melakukan ruwatan?”(Sang Pencerah, 2010: 71).
Darwis berpikir keras untuk mencari jawaban atas
kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekitar masyarakat
Kauman. Namun, posisi orang tuanya (Kiai Abu Bakar)
sebagai Imam dan Khatib Masjid Gedhe Kauman juga cukup
membantu proses pendewasaan Darwis. Sebagai anak kiai
besar, Darwis memiliki banyak kesempatan untuk
berinteraksi dengan kalangan kiai-kiai lainnya. Dalam
interaksinya dengan kiai-kiai tersebut semakin banyak hal
yang mengganggu pikiran Darwis mengenai cara berislam
mereka.
Dalam perjalanannya, Darwis bertemu dengan
beberapa orang Kiai, antara lain: pertama, Kiai Abdul Hamid
Lempuyangan yang dikaguminya karena kebiasaannya
memberikan makan anak-anak yatim piatu. Sebagai anak
yang kritis, di dalam kepala Darwis timbul pertanyaaan,
mengapa Kiai Hamid memiliki kebiasaan tersebut. Namun,
68
melalui penjelasan yang singkat dari Kiai Hamid, Darwis
merasa puas dengan jawaban dari pertanyaan yang dia
simpan sendiri.
(c) Gawatan (rising action)
Setelah tahap rangsangan (inciting moment) kemudian
dilanjutkan dengan tahap gawatan (rising action) merupakan
bagian dari alur yang menunjukkan gerak menanjak masalah.
Tahapan ini menunjukkan pertemuan Kiai Dahlan dengan Kiai
Noor yang tidak lain adalah keluarganya sendiri. Kiai Noor
banyak memberikan pelajaran tentang sejarah penjajahan
Belanda di wilayah Nusantara. Informasi tersebut menjadi
bekal bagi Kiai Dahlan dalam mendirikan organisasi
Muhammadiyah (Sang Pencerah, 2010:205-206).
2) Tengah
(a) Tikaian (confict)
Tahap tikaian (confict) menggambarkan perbedaan sikap,
keinginan, dan pandangan masalah para tokoh. Pada tahap ini
digambarkan pada saat Darwis mendapati tradisi-tradisi yang ada
pada masyarakat. Tradisi ruwatan dan sesajen merupakan
tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat dan dilestarikan
oleh para kiai-kiai termasuk yang difasilitasi oleh pengurus
Masjid Gedhe Kauman. Tradisi tersebut turut menambah
deretan pertanyaan yang menumpuk di kepala Darwis.
69
Menurutnya, tradisi semacam itu hanya membuang-buang
uang.
“Maksudnya sederhana itu cukup berdoa saja, Pak.Tidak perlu dengan upacara berlebihan apalagidengan memberikan sesajen”. Aku memantapkanhatiku dalam memberikan jawaban sambil tetapberusaha menjaga kesantunan. “uang pembuatansesajen itu bisa dimanfaatkan sebagai sedekah bagifakir miskin sehingga hasilnya juga akan lebih jelas”(Sang Pencerah, 2010: 84).
Gugatan Darwis tersebut dikemukakan di depan rapat
akbar tahunan menjelang datangnya bulan Ramadhan yang
dihadiri oleh para kiai besar, seperti Kiai Abu Bakar dan Kiai
Penghulu Khalil Kamaludiningrat. Mendengar komentar
Darwis, beberapa orang Kiai berkomentar sinis, termasuk di
antaranya adalah Kiai Noor dan Kiai Kamaludiningrat.
Diskusi tersebut tidak selesai begitu saja, Kiai Abu
Bakar yang tidak lain adalah orang tua Darwis, menyimpan
amarah dan mengungkapkannya ketika sampai di rumahnya.
Debat pun tidak dapat dihindarkan. Kiai Abu Bakar juga
menghardik Darwis yang menganggap sebagai anak yang
memalukan. Sementara itu, Darwis bertahan dengan
pendapatnya dalam menyikapi tradisi Nyadran dan Ruwatan.
Kiai Abu Bakar menyarankan agar Darwis tidak hanya
menggunakan akalnya dalam mengemukakan pendapat
menyangkut agama, tetapi juga menggunakan hati. Kemudian
70
ia menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam menanyakan
hal-hal yang sensitif.
(b) Rumitan
Tahap rumitan (complication) menunjukkan tikaian
yang semakin tajam dan rumit. Setelah kepulangannya dari
Makkah, Kiai Dahlan yang telah menimba berbagai ilmu
termasuk ilmu falak dan hisab mencoba untuk memeriksa
arah kiblat yang ada di tanah Jawa termasuk di masjid Gedhe
Kauman. Dari pemeriksaannya, diketahui bahwa beberapa
masjid di Jawa arah kiblatnya melenceng dan tidak
menghadap kiblat, melainkan menghadap persis ke arah barat
tepatnya ke negara Mekah.
Kegelisahannya tersebut mula-mula dikemukakan
kepada Kiai Saleh. Dalam sebuah pembicaraan serius
tersebut, Kiai Dahlan mengemukakan pendapatnya mengenai
arah kiblat masjid-masjid yang ada di Jawa termasuk Masjid
Gedhe Kauman yang salah. Sebagai sesama orang yang
pernah belajar ilmu falaq, Kiai Shaleh menerima masukan
dari Kiai Dahlan dan mengemukakan pendapatnya untuk
mempertemukan dengan Kiai Noor. Pertemuannya dengan
Kiai Noor membuat perdebatan yang cukup sengit.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk merapatkan
dengan kiai-kiai lainnya sesuai dengan tawaran Kiai Noor.
71
“Dan kamu juga harus siap jika dalam pembicaraannanti ternyata para kiai, umpamanya menolak usulanDimas untuk mengubah arah salat ini. Sebab bisa sajaperhitungan Dimas ini benar secara akal untuk arahkiblat, tapi para kiai punya pertimbangan lain yanglebih luas daripada sekadar kompas” (Sang Pencerah,2010: 204).
Dalam rapat yang dihadiri oleh kiai-kiai besar
tersebut, Kiai Dahlan mengemukakan temuannya mengenai
arah kiblat yang dianggap melenceng. Hadir dalam rapat
tersebut adalah kiai-kiai yang ahli ilmu falaq, yaitu Kiai Haji
Raden Dahlan dari Termas, Pacitan, dan Sayid Usman Al-
Habsyi yang tinggal di Batavia.
Selesai presentasi, Kiai Siraj mengutarakan
pandangannya. Ia mengatakan
“Maaf Kiai Dahlan. Kiblat itu bukan soal arah, tapisoal kalbu,” “Allah Jumeneng tidak diukur letaknyaberdasarkan arah, karena Allah berada di dalam kalbuumat” (Sang Pencerah, 2010:206).
Pendapat Kiai Siraj tersebut disetujui oleh kiai yang
hadir seperti Kiai Muhammad Faqih. Walaupun pertanyaan-
pertanyaan tersebut telah dijawab dengan menunjukkan peta
dunia, tidak semua puas dengan jawaban Kiai Dahlan, seperti
Kiai Abdullah dari Blawong yang mempertanyakan hal yang
sama, “Kalau begitu, mengapa saat ini semua masjid di
Nusantara ini memiliki arah kiblat ke arah Barat Kiai
Dahlan?”
72
Pertanyaan senada juga diutarakan oleh Kiai
Penghulu Kamaludiningrat yang mengatakan sebagai berikut:
“Maaf Kiai Dahlan, saya masih yakin bahwa NgarsaDalem Sri Sultan Hamengkubuwono I yangmemerintahkan pembangunan Masjid Gedhe ini tidakceroboh soal arah kiblat. Beliau pasti sudah banyakberkonsultasi dengan para kiai terdahulu yang jugamengerti ilmu falaq dan hisab, serta tidak asal-asalanmembangun posisi masjid tanpa perhitungan” (SangPencerah, 2010: 211).
(c) Klimaks
Pada tahap klimaks (climax) menunjukkan ketajaman
konflik yang dihadapi para tokoh. Diskusi mengenai arah
kiblat tersebut menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kiai
Dahlan merasakan adanya perubahan pada sikap Kiai Noor
dan Kiai Muhsin terhadap dirinya. Ia merasa usulannya telah
menjadi penyebab perubahan sikap mereka.
Perselisihan memuncak ketika Kiai Penghulu
Kamaludiningrat melihat adanya penanda arah kiblat yang
ditulis dengan kapur. Kiai Penghulu marah besar melihat
adanya tanda tersebut dan tuduhannya mengarah pada pihak
Kiai Dahlan. Kemudian, ia memerintahkan marbut untuk
memanggil Kiai Dahlan. Dalam pertemuan itu juga
disaksikan oleh beberapa orang murid Kiai Dahlan dan Kiai
Penghulu yang biasa mengaji di Masjid tersebut.
“…lihat itu!” ujar kiai Kamaludiningrat dengan suarabergetar menunjuk kearah lantai. Sebuah garis safbaru dari kapur terlihat di atas lantai dengan posisi
73
miring 44” ke arah barat laut” (Sang Pencerah, 2010:215).
Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba terdengar
suara keras yang mengaku sebagai pelaku. Dirjo, adalah
pelaku pembuat saf baru yang menyebabkan kemarahan Kiai
Kamaludiningrat. Mengetahui pelakunya adalah Dirjo yang
tak lain adalah keponakan Kiai Penghulu sendiri, ia kemudian
meminta maaf kepada Kiai Dahlan.
Kejadian perselisihan antara Kiai Dahlan dan Kiai
Penghulu Kamaludiningrat itu berakibat pada kepercayaan
jamaah. Hal tersebut terlihat dari menambahnya jamaah
tarawih di Langgar Kidul dan menurunnya jamaah tarawih
Masjid Gedhe. Beberapa anak-anak yang biasa berjamaah di
Masjid Gedhe pindah ke Langgar Kidul milik Kiai Dahlan,
bukan hanya karena bilangan rakaatnya lebih sedikit,
melainkan juga karena mungkin ada pertimbangna lainnya.
Bahkan, ada jamaah yang berasal dari luar Jogja menunaikan
salat tarawih di Langgar Kidul.
Hal tersebut membuat para pengikut Kiai Penghulu,
yaitu Kiai Noor menanyakan secara khusus kepada Kiai
Dahlan. Bahkan, ia sempat menuduh kalau Kiai Dahlan
mngajarkan untuk menjauhi Masjid Gedhe, walaupun hal
tersebut langsung ditepis oleh Kiai Dahlan. Berdasarkan
desas-desus yang diterima oleh Kiai Noor bahwa Kiai Dahlan
74
adalah Kiai kafir, maka dalam pertemuan tersebut Kiai Noor
menyarankan agar Kiai Dahlan mengubah caranya
berdakwah seperti umumnya Kiai Kauman.
Perselisihan tersebut berujung pada permintaan
pembongkaran Langgar Kidul oleh Kiai Penghulu
Kamaludiningrat. Kiai Kamaludiningrat mengirim surat
sebanyak dua kali kepada Kiai Dahlan dengan isi yang sama
yaitu perintah membongkar Langgar Kidul. Kiai Dahlan
menjawab surat dengan berpesan kepada pengantar surat
bahwa langgarnya tidak akan ditutup. Menyikapi sikap Kiai
Dahlan yang tetap dengan pendiriannya, dan setelah tiga kali
diperingatkan dan diancam, Kiai Kamaludiningrat
memerintahkan orang-orang suruhannya untuk membongkar
paksa Langgar Kidul.
Sekali lagi aku mengulang jawaban semalam.“sampaikan kepada kiai Penghulu bahwa langgar initidak akan saya tutup” (Sang Pencerah, 2010: 235).
Rombongan suruhan Kiai Penghulu mulai memasuki
halaman Langgar Kidul. Para santri yang sedang bertadarus
langsung berhenti saat salah satu orang suruhan Kiai
Penghulu mencari Kiai Dahlan.
Rombongan suruhan Kiai Penghulu memasukihalaman Langgar Kidul. Sayup-sayup suara tadarusmasih terdengar sebelum suara keras tiba-tibaterdengar menghentak.” Mana Kiai kafir itu!” (SangPencerah, 2010: 244).
75
Mereka kemudian langsung mengayunkan alat yang
mereka bawa ke dinding Langgar Kidul untuk dihancurkan.
Orang-orang itu pun langsung mengayunkan linggis,cangkul, martil, dan apapun peralatan yang merekabawa ke dinding (Sang Pencerah, 2010: 245).
3) Akhir
(a) Leraian (falling action)
Pada tahap leraian (falling action) menggambarkan
mulai cairnya kebekuan dan kekakuan sikap para tokoh yang
terjadi hingga klimaks. Pada tahap ini digambarkan setelah
pembongkaran Langgar Kidul Kiai Dahlan memutuskan untuk
pergi dari Kauman. Kaputusan pindah akhirnya diambil,
hingga datanglah Kiai Shaleh dan Nyai Shaleh yang meminta
Kiai Dahlan dan Nyai Walidah untuk membatalkan niatnya.
Dengan janji untuk membangun kembali Langgar Kidul,
akhirnya Kiai Dahlan benar-benar mengurungkan niatnya.
“Demi Allah Dahlan, cuma sekali ini mbakmemintamu,” kata Nyai Saleh kali ini dengan sangattegas. “Seorang pemimpin yang baik di mata Allahtidak akan pernah meninggalkan keluarga danumatnya, sebesar apaun kesulitan yang sedangdihadapinya (Sang Pencerah, 2010: 260).
Kiai Dahlan kembali membangun langgarnya berkat
bantuan Kiai Shaleh dan Kiai Ibrahim. Dukungan kedua
keluarganya terutama Kiai Ibrahim selaku mantan Kiai
Penghulu Masjid Gedhe telah mengangkat moral Kiai Dahlan
76
untuk melanjutkan dakwahnya dan mendirikan kembali
langgarnya.
“…..seperti sudah aku janjikan di kereta api tadi, akuakan membangun lagi Langgarmu.” Mas Saleh lalumengeluarkan kantong-kantongdan mneumpahkanseluruh isi kantong ke atas meja. “ini tabunganku,silakan kamu gunakan untuk membangun lagiLanggarmu secepatnya (Sang Pencerah, 2010: 262).
Setelah berdirinya Langgar Kidul tersebut, kiai Dahlan
kembali menjalankan aktifitasnya dalam memberikan
pengajian kepada santri-santrinya. Setelah kegiatan
pengajiannya berjalan lancar, Kiai Dahlan menemui Kiai
Penghulu yang dulu memerintahkan penghancuran Langgar
Kidul. Dalam pertemuannya tersebut, Kiai Dahlan
mengemukakan keinginannya untuk mundur dari jajaran
pengurus Masjid Gedhe Kauman.
(b) Selesaian (denaument)
Tahap selesaian (denaument) memberikan gambaran
nasib para tokoh terhadap penyelesaian. Pada tahap ini semua
konflik terselesaikan. Pada tahap ini digambarkan saat Kiai
Dahlan berkeinginan untuk membentuk suatu organisasi Islam.
Ide pembentukan organisasi yang beranggotakan orang Islam
sudah ada sebelum bergabungnya kiai Dahlan dengan Budi
Utomo, tetapi Kiai Dahlan belum mengetahui cara
mengaturnya. Ide itu kembali muncul setelah diskusi dengan
seorang anak yang menganjurkan untuk membuat suatu sistem
77
dalam lembaganya (di Langgar Kidul) agar kelak ketika
meninggal ada penerusnya.
Keinginan tersebut diutarakan dalam sebuah pertemuan
yang dihadiri oleh Sangidu, Hisyam, Fahrudin, Sudja, dan Siraj.
Terjadi diskusi di antara mereka soal nama. Akhirnya, usul
Fahrudin yang diterima adalah Muhammadiyah. Izin pendirian
organisasi Muhammadiyah segera dilayangkan kepada
Rykberstuur der Yogyakarta Patih Dalem Sri Sultan yang
ditandatangani oleh Kiai Dahlan selaku Presiden
Muhammadiyah. Sultan menyetujui usulan tersebut dan
menyarankan untuk tidak mengecilkan kedudukan Masjid
Gedhe Kauman.
“Kamu Du” ujarku sambil menatap Sangidu. Adiktiriku terlihat sedang memikirkan sesuatu sebelumsebaris kalimat meluncur dari mulutnya. “Kalau akuusulkan namanya Muhammadiyah” (Sang Pencerah,2010: 417).
Sri Sultan menyetujui pendirian Muhammadiyah dan
mendoakan semoga organisasi itu dapat mendatangkan manfaat
bagi umat Islam.
“Baiklah Kiai Dahlan. Semoga perkumpulan yangakan Kiai dirikan ini benar-benar mendatangkanmanfaat bagi umat Islam khususnya di Yogyakarta(Sang Pencerah, 2010, 424).
Sebagai organisasi Islam baru, biasanya dimintakan
persetujuan dari Kiai Penghulu Kholil Kamaludiningrat.
Diadakanlah suatu musyawarah di antara para kiai pengurus
78
Masjid Gedhe Kauman. Sempat terjadi salah paham
menyangkut isi surat Kiai Dahlan. Para Kiai tersebut, terutama
Kiai Penghulu memahami membaca Presiden dengan Residen.
Kesalahpahaman tersebut berujung pada penolakan organisasi
Muhammadiyah. Namun, setelah semuanya diluruskan barulah
dibolehkan izin pendirian Muhammadiyah.
d. Latar
1) Latar Tempat
Latar tempat yang digunakan dalam novel Sang Pencerah
cukup bervariasi dan mendukung nilai-nilai religius yang terdapat
dalam novel. Latar tempat yang digunakan dalam novel Sang
Pencerah adalah Serambi Masjid Gedhe, Masjidil Haram, Langgar
Lor, Langgar Kidul, Kweek School.
a) Di Serambi Masjid Gedhe
Pengarang menggambarkan secara utuh Serambi Masjid
Gedhe misalnya ada suara anak perempuan yang sedang
membaca Alquran di serambi Masjid Gedhe Kauman yang
selalu membawa keheningan. Lantunan ayat Alquran yang
dapat menyejukkan hati orang yang mendengarnya diibaratkan
seperti aliran sungai yang jernih, sedangkan anak lelaki
bermain bola di sekitar Serambi Masjid. Latar Serambi Masjid
Gedhe berhubungan dengan latar waktu yaitu anak-anak
mengaji pada sore hari/senja.
79
“Suara anak-anak perempuan yang sedang belajarmembaca Alquran di serambi Masjid Gedhe Kaumanselalu membelah keheningan senja di kawasan sepertialiran sungai yang bening, jernih, menyejukkan (SangPencerah, 2010:6).
b) Masjidil Haram, Makkah
Masjidil haram merupakan tempat Kiai Dahlan
menimba ilmu dan bertemu dengan beberapa kalangan ilmuan
yang berpengaruh.
“Dan sekarang aku sedang berada bersama puluhanmurid lain dari berbagai Negara di salah satu bagianruangan Masjidil Haram, mendengarkan pelajaranyang disampaikan ulama bernama lengkap SyaikhAhmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi As-Syafi’i…” (Sang Pencerah, 2010:141).
Lima tahun Kiai Dahlan menimba ilmu di Mekah dan
rasanya baru kemarin beliau belajar dan tiba saatnya beliau
untuk pulang.
“Tak terasa sudah lima tahun aku menimba ilmu diMakkah.” (Sang Pencerah, 2010:143).
c) Di Langgar Lor
Pengajian yang rutin dilakukan kiai Dahlan di Langgar Lor
masih seperti biasa dengan jumlah murid yang cukup banyak.
Pengajian di Langgar Lor masih berlangsung sepertibiasa, dengan para murid yang cukup banyak (SangPencerah, 2010:267).
d) Di Langgar Kidul
Langgar Kidul merupakan tempat mengajar Kiai Dahlan
dan berdakwah kepada masyarakat. Dalam pengajian di Langgar
80
Kidul Kiai Dahlan mengangkat kejadian di Alun-alun mengenai
banyaknya kemiskinan dan orang tua yang tidak bisa mendidik
anak.
Sebagai topik bahasan di pengajian Langgar Kidul,Kiai Dahlan mengangkat kejadian di Alun-alun Utaratentang banyaknya kemiskinan serta orang tua yangtidak bisa mendidik anak. Dalam pengajian diLanggar Kidul pada sorenya, aku mengangkatkejadian di Alun-Alun Utara itu sebagai bahasan(Sang Pencerah, 2010:402).
e) Di Kweek School
Kweek School merupakan sekolah untuk orang-orang
yang termasuk ke dalam golongan priyayi. Pengarang secara
utuh menggambarkan Kweek School misalnya ada kelas, meja,
dan murid. Kiai Dahlan untuk pertama kalinya mengajar di
Kweek School dengan materi kentut yang akhirnya membuat
jadwal mengajar Kiai Dahlan di Kweek School semakin sering.
Beliau mengajarkan ajaran Islam yang disampaikannya melalui
tanya jawab.
“Jadwal mengajarku di Kweek School Jetis jadisemakin sering. Dan murid-murid yang rata-rataberumur 13 tahun ini pun semakin terbiasamendegarkan ajaran Islam ynag kusampaikan lewattanya jawab yang cair” (Sang Pencerah, 2010:403).
2) Latar waktu
Latar waktu yang digunakan dalam novel Sang Pencerah
cukup bervariasi dan cukup lengkap. Latar waktu yang digunakan di
81
dalam novel tersebut adalah waktu/jam, pagi hari, siang, sore,
malam, hari, bulan, dan tahun.
a) Waktu/jam
Penggunaan latar waktu/jam digunakan ketika
menunjukkan lamanya perjalanan yang ditempuh Darwis dari
Jogja ke Semarang yaitu sekitar enam jam seperti disebutkan di
dalam kutipan berikut:
“Perjalanan awal sekitar enam jam menempuh jarakJogja-Semarang pun usai. Waktu menunjukkansekitar pukul empat sore” (Sang Pencerah,2010:125).
Selain jam, waktu yang digunakan adalah yang merujuk
pada lamanya suatu pekerjaan dilakukan, seperti waktu lama,
sebentar dan lain-lain. Dalam kutipan di bawah ini misalnya
digunakan waktu lama untuk menunjuk rentang waktu yang
digunakan.
“Lama sekali aku dan walidah membicarakan hal inisemalam, melihat dari berbagai kemungkinan yangbisa terjadi dengan tepatnya kami di sini atau kamipergi” (Sang Pencerah, 2010:254).
b) Pagi hari
Latar waktu yang digunakan juga misalnya menunjuk pada
waktu pagi hari. Seperti kutipan di bawah ini:
“Esok harinya bapak pulang pagi seperti disebutkanibu. Beliau membahawakan banyak barang bagi kamiberdua.” (Sang Pencerah, 2010:100).
82
c) Siang
Waktu siang digunakan ketika Walidah merasakan ibunya
tidak menyebutkan nama Darwis selama seharian. Ia kangen
dengan nama itu, seperti terlihat pada kutipan berikut ini:
“Repotnya dari tadi siang ibu sama sekali takmenyebu-nyebut nama Mas Darwis. Beliau sibuk didapur mempersiapkan makanan berbuka untuk bapakdan kami semua” (Sang Pencerah, 2010:96).
d) Sore
Waktu sore sangat sering digunakan untuk menunjuk pada
waktu sebelum petang. Penggunaan waktu sore dijumpai di dalam
penyebutan kegiatan anak-anak santri di Masjid Gedhe seperti
kutipan berikut:
“Setiap sore terdengar pengajian anak-anak putri dariarah serambi Masjid Gedhe” (Sang Pencerah,2010:21).
Walidah memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama
teman-temannya untuk membatik.
“Akhirnya, sore itu aku habiskan waktu di belakangrumah bersama Ginah dan tiga temannya yang biasamembatik untuk bahan jualan bapak” (SangPencerah, 2010: 101).
e) Malam
Penggunaan waktu malam juga digunakan untuk menunjuk
waktu kira-kira habis magrib hingga fajar, seperti kutipan di
bawah ini.
“O… kalau soal itu tanya mas Darwis,“ Jawabkusetenang mungkin, “Aku, si siap saja. Mau malam ini
83
dilamarnya juga hayuk,” jawabku yang membuatmereka semakin tertawa terpingkal-pingkal.“Malam itu, aku sedang merapikan catatan penjualanbatik dalam sebulan, dan mencocokkannya denganuang gulden yang ada dalam kotak penyimpanan hasilpenjualan batik selama ini”. (Sang Pencerah,2010:160).
f) Hari
Latar waktu hari digunakan untuk menyebut hari secara
umum dan hari secara spesifik. Contoh waktu hari secara umum
misalnya pada kutipan pertama, sedangkan kutipan kedua
menunjuk pada waktu hari secara spesifik yaitu hari sabtu.
“Hari demi hari berlalu, dan akhirnya menembus satupekan pelayaran, lalu menembus 10 hari, lalu 14 hari,dan selanjutnya sampai pada hari kelima belas (SangPencerah, 2010:137).
Peresmian didirikannya organisasi Muhammadiyah yakni
hari sabtu terakhir bulan Desember tahun 1912.
“Hari Sabtu malam Minggu terakhir bulan Desember1912 (Sang Pencerah, 2010:454).
g) Bulan
Latar waktu bulan digunakan juga secara spesifik dan
umum. Dalam kutipan berikut misalnya ditunjukkan waktu bulan
Hijriyah dan Masehi.
“Akhirnya pada Rajab 1891 bapak melangsungkanpernikahan keduanya dengan Ibu Raden KhatibTengah Haji Muhammad.” (Sang Pencerah,2010:164).
Pada 12 November 1912 murid-murid Kiai Dahlan
berkumpul untuk membahas Muhammadiyah.
84
“Akhirnya pada 12 November 1912 sekitar 30 orangmuridku dari berbagai umur berkumpul. (SangPencerah, 2010:450).
h) Tahun
Penggunaan latar waktu tahun cukup banyak dijumpai di
dalam novel Sang Pencerah. Latar waktu tahun digunakan pada
kutipan-kutipan berikut:
“Aku lahir pada 1868, atau 10 tahun lalu, ketikamasyarakat Yogyakarta masih belum lupa pada linduyang mengoyak wilayah mereka setahun sebelumnya”(Sang Pencerah, 2010:11).
Kiai Dahlan merasa waktu begitu cepat berputar,
pernikahannya dengan Walidah berjalan setengah tahun dan
Walidahpun sudah hamil tiga bulan.
“Waktu berjalan cepat. Tak terasa pernikahan sudahberjalan hampir setengah tahun. Walidah sendirisudah hamil tiga bulan. Untunglah proses kehamilanberjalan lancar tak ada hal-hal serius yang berkaitandengan kesehatannya” (Sang Pencerah, 2010 :160).
Kebahagiaan Kiai Dahlan terasa lengkap saat beliau
berumur 22 tahun, beliau dikaruniai seorang putri yang kemudian
diberi nama Siti Johanah.
“Pada 1890 saat umurku 22 tahun, Allahmenggenapkan kebahagiaanku dengan menjadikankusebagai seorang bapak lewat kelahiran putri pertamayang kuberi nama Siti Johanah binti Ahmad Dahlan”(Sang Pencerah, 2010:161).
Berdasarkan uraian latar waktu di atas, terlihat bahwa novel
Sang Pencerah menggunakan berbagai bentuk dan macam waktu.
Hal tersebut terasa indah ketika dibaca. Karena penggunaan
85
waktu secara lengkap, maka novel tersebut berhasil
menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang tampak mendekati
kebenaran peristiwanya.
3) Latar sosial
a) Seorang Khatib Masjid
Kiai Abu Bakar dan Kiai Dahlan merupakan Imam dan
Khatib Masjid Gedhe Kauman.
“Silahkan tunggu Kiai,” ujar seorang penggawakeratin dengan nada hormat kepada Kiai Dahlan yangmenjabat sebagai Khatib Masjid Gedhe Kauman”(Sang Pencerah, 2010:2).
b) Seorang Penghulu
Seorang penghulu ada dalam tokoh Kiai Kamaludinigrat.
Penghulu adalah jabatan penting yang bisa membuatnya
bertemu muka dengan Sri Sultan yang berjuluk Senopati
Ngalogo Sayidan Panatagama Khalifatullah.
“Kanjeng Sri Sultan memasuki masjid diikuti KiaiPenghulu Kamaludiningrat, bapakku Kiai Abu Bakar,beberapa ulama keraton, dan para punggawa yangmengantarkannya sampai depan pintu Maksura.Setelah Kanjeng Sayyidin Panatagama Khalifatullahitu memasuki Maksura, barulah para Kiai danpunggawa menempati tempat duduk masing-masing”(Sang Pencerah, 2010: 62).
c) Seorang Khatib Amin
Seorang Khatib Amin Masjid Gedhe ada dalam tokoh
Kiai Abu Bakar dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Khatib Amin
atau Tibamin adalah pengkhutbah utama dalam salat Jumat.
86
Kutipan berikut terlihat Darwis saat melihat Kiai Abu Bakar
berkhutbah dalam salat jumat.
“Dari atas mimbar itulah wajah bapakku yangberpengetahuan tinggi tetapi sangat rendah hati, selalumenyempatkan untuk menatap wajahku walau sesaatdi tengah penuhnya jamah. Pancaran sinar matanyaseakan menyampaikan pesan, “Inilah garis hidup kitaNak, untuk terus menyebarkan ajaran mulia agamaAllah Swt setiap saat” (Sang Pencerah, 2010:10).
Untuk pertama kalinya Kiai Dahlan berkhutbah di depan
para jamaah dan merupakan pengalaman baru baginya dan juga
orang-orang yang menunaikan salat Jumat tidak terkecuali bagi
Sri Sultan.
“Akhirnya, datang juga kewajibanku untukmemberikan khutbah Jumat di Masjid GedheKauman. Ini merupakan pengalaman baru bagi kamisemua yang menunaikan shalat Jumat di MasjidGedhe, tak terkecuali bagi Sri Sultan yang berada didalam Maksura, tempat khusus yang diperuntukkanbaginya.” (Sang Pencerah, 2010:174).
Kiai Dahlan saat memberikan khutbah Jumat
memperhatikan wajah para jamaah termasuk Kiai Penghulu
yang terlihat sedang menatapnya.
“Allah Swt berfirman bahwa Islam adalah rahmatanlil’alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, “ujarkumembuka khutbah Jumat.“Islam harus menjadirahmat bagi siapa saja yang bernaung di dalamnya,baik Muslim maupun bukan Muslim. “Aku pandangiwajah jamaah, termasuk Kiai PenghuluKamaludiningrat yang sedang menatapku dalam-dalam” (Sang Pencerah, 2010:175).
87
d) Seorang Pedagang Batik
Seorang pedagang batik ada dalam tokoh Kiai Fadlil dan
Kiai Ahmad Dahlan. Dalam berdagang, Kiai Fadlil dikenal
sebagai sosok yang jujur dan melayani sangat memperhatikan
pembelinya. Sebagai pedagang ia termasuk pedagang yang
bertanggung jawab, seperti kutipan di bawah ini:
“Kiai Haji Muhammad Fadil itu pedagang yangbertanggungjawab, Bu. Beliau tidak mau menjualbarang yang jelek semata-mata untuk mengejarkeuntungan duniawi. Buat beliau berdagang itu adalahibadah.” (Sang Pencerah, 2010:46).
Siti Walidah merupakan anak dari Kiai Haji Muhammad
Fadlil. Beliau merupakan kakak dari ibu Darwis yang dikenal
sebagai pedagang kain batik.
“Namaku Siti Waliddah binti Muhammad Fadlil. Ya,orang tuaku adalah Kiai Haji Muhammad Fadlil, Kiaiyang juga dikenal sebagai pedagang kain batik. Ibukudipanggil orang-orang, Nyai Fadlil (Sang Pencerah,2010: 93).
Aktivitas berdagang juga dilakukan oleh Kiai Ahmad
Dahlan. Pascapernikahannya dengan Nyai Walidah, Kiai Dahlan
membantu dan meneruskan bisnis mertuanya sebagai pedagang
batik. Aktivitas itu dilakukan di luar kesibukannya sebagai guru
mengaji dan Khatib di Masjid Gedhe Kauman.
“Di luar kesibukanku mengajar di Langgar Kidul danmenjadi Khatib Masjid Gedhe, kegiatanku yang lainadalah berdagang batik. Pekerjaan ini membuatkubanyak mengunjungi daerah-daerah, termasuk Bantulseperti sore ini.” (Sang Pencerah, 2010:190).
88
e) Seorang Penulis Produktif
Seorang penulis produktif ada dalam tokoh Kiai Sholeh
Darat. Kiai Soleh Darat adalah guru dan juga teman dari Kiai
Abu Bakar yang tinggal di Semarang.
“Kembali ke Kiai Sholeh Darat, beliau juga seorangpenulis produktif. Selain menulis kitab Faid Ar-Rahman, Kiai menulis sejumlah karya lain sepertiMajmu’an Ay-Syariah Al-Kafiyah Li AL-‘Awam(membahas ilmu-ilmu syariat untuk orang-orangawam), Munjiyat (tentang tasawuf, yang merupakanpetikan-petikan penting dari Ihya’ Ulum Ad-Dinkarya Imam Al-Ghazali) dan Al-Hikam karanganSyaikh Ibnu ‘Athaillah Al-Askandari)” (SangPencerah, 2010:129).
f) Seorang Ketua Raad Agama
Seorang ketua Raad Agama ada dalam tokoh Kiai
Penghulu Kholil Kamaludingrat.
“Iya, saya tahu. Tapi bagaimana sebagai ketua RaadAgama, Kiai Penghulu bisa menjelaskan kepada sayaapa alasan utama yang menjadi dasar penolakankarena Sri Sultan sendiri ingin tahu soal itu.” (SangPencerah, 2010:441).
e. Amanat
Dari sebuah karya sastra dapat diangkat suatu ajaran moral, atau
pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerita
biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan
ajaran moral tertentu. Amanat pada sebuah karya sastra ditampilkan
secara implisit (tak langsung) ataupun eksplisit (langsung) (Sudjiman,
1988: 57).
89
Adapun amanat yang penulis temukan di dalam novel Sang
Pengeran adalah sebagai berikut:
1) Tidak Boleh Menyekutukan Allah dengan Makhluk-Nya
Salah satu ritual yang masih berkembang di tengah-tengah
masyarakat kita adalah ritual mempersembahkan tumbal atau
sesajen kepada makhuk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu
atau penguasa tempat keramat. Kebiasaan tersebut merupakan
perbuatan yang mengandung syirik (menyekutukan Allah Swt.
dengan makhluk). Praktik ini merupakan pengejawantahan
keyakinan mereka kepada makhluk halus yang dianggap memiliki
kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan
malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan
tumbal atau sesaji tersebut mereka berharap dapat meredam
kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka
dipenuhinya.
Perbuatan inilah yang masih berkembang di masyarakat
ketika Kiai Dahlan kecil. Praktik ini terlihat jelas di dalam diskusi
berikut ini:
“Pulang dari Masjid Gedhe, aku melihat sepasang suami-isteri memberikan sesaji dan membakar kemenyan di antarapohon beringin dengan sangat hati-hati.”“Aku dekati pohon beringin itu dengna berjalan sewajarmungkin, sebelum mengendap-ngendap dan dengan cepatmengambil sesajen dan kembali bertingkah sewajarmungkin seperti sebelumnya.”“tanpa kuduga, belum jauh aku beranjak, pasangan suamiisteri itu dating lagi. “lho kok, sesajennya hilang, pak?” serisi isteri terdengar kaget. “apa dicuri orang ya?”
90
“Hus! Jangan asal ngomong, Bu. Itu artinya sesajen kitaditerima. Niat kita direstui.” (Sang Pencerah, 2010:90).
Di dalam Islam, ritual sesaji diharamkan karena
mengandung perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan
makhluk-Nya, seperti firman Allah di dalam QS al-Jin ayat 6
berikut ini:
نس یعوذون برجال من الجن وأنھ كان رجال من اإلفزادوھم رھقا
“Bahwasannya ada beberapa orang dari (kalangan) manusiameminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari(kalangan) jin, maka jin-jin itu menambah bagi merekadosa dan kesalahan” (QS al-Jin: 6).
Orang-orang pada zaman Jahiliyah meminta perlindungan
kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan
penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih
hewan kurban (sebagai tumbal), bernadzar, meminta pertolongan
dan lain-lain. Praktik semacam ini telah dilarang dan merupakan
perbuatan dosa besar yang tidak diampuni Allah.
2) Tidak Boleh Menuduh Kafir terhadap Sesama Muslim
Kiai Dahlan beberapa kali dituduh kafir oleh masyarakat
sekitar dan oleh sebagian kiai yang memang kontra terhadap tindak
tanduknya, seperti Kiai Noor, Kiai Muhsin dan Kiai Penghulu.
Tuduhan Kiai Noor misalnya tergambar dari kutipan berikut:
“Apakah kau belum pernah dengar kabar-kabar yangmengatakan, maaf ya Dimas Dahlan, bahwa Dimas adalahkaii kafir mulai dari bermain biola di Langgar, sampaiberbagai protes yang Dimas lakukan hampir setiap waktu
91
terhadap berbagai tradisi yang sudah mengakar dimasyarakat dan mendapatkan restu Ngarsa Dalem, dansekarang ditambah lagi dengan soal perubahan arah kiblat?”(Sang Pencerah, 2010:229).
Kiai Noor biasanya tegas dalam menegur Kiai Dahlan
dalam soal-soal yang menyangkut pada akidah. Dalam kutipan di
atas, jelas-jelas bahwa tuduhan kafir yang dialamatkan kepada Kiai
Dahlan merupakan akumulasi dari kegelisahannya mengenai kabar-
kabar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya,
Kiai Noor menanyakan dan menegur langsung Kiai Dahlan seperti
terlihat di dalam kutipan di atas.
Tuduhan kafir kembali terjadi ketika Kiai Dahlan
bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan mengajar di
Kweekschool. Pergaulannya dengan banyak kalangan
menyebabkan adaptasi cara berpakaian Kiai Dahlan, seperti sering
memakai jas dan lain-lain. Oleh karena itu, penampilannya tersebut
membuat sebagian kalangan masyarakat dan beberapa orang Kiai
resah. Hal tersebut misalnya terlihat dari uraian berikut ini:
“Wajar saja Dimas Dahlan kalau masyarakat bertanya-tanya mengapa Dimas sekarang sering terlihat memakai jas,dasi, sepatu. Mirip pakaian orang kafir, tapi pakai serbanjuga, “ujar Mas Muhsin (Sang Pencerah, 2010:391).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
selama berdakwah, Kiai Dahlan sebanyak dua kali dituduh kafir
oleh masyarakat dan para kiai yang beroposisi. Perbuatan tersebut
92
jelas bertentangan dengan ajaran Islam seperti disebutkan dalam
hadis Riwayat Ahmad berikut ini:
من كفر أخاه فقد باء بھا أحدھم
“Siapa saja yang mengkafirkan saudaranya, maka berbalik
kepada salah satu di antara mereka.” (HR Ahmad).
Tuduhan-tuduhan (menyesatkan dan mengkafirkan) seperti
ini sangat berbahaya bagi seorang muslim, apalagi tuduhan
kekufuran atau sesat tersebut merupakan tuduhan yang sangat
sensitif bagi kaum muslim yang lain. Oleh karena itu, jika tuduhan
tersebut dilakukan tanpa bukti yang kuat di sisi Allah, ini termasuk
dalam kategori fitnah yang dilarang dalam hadis Nabi saw.
ع مسلما ال یحل لمسلم أن یرو
“Tidak halal bagi seorang Muslim memburuk-burukkan
Muslim yang lain” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ath-Thabrani).
Hal ini tidak berarti menuduh sesat seseorang yang memang
terbukti secara qath‘i (jelas) sesat atau kufur itu tidak dibolehkan.
Dalam Islam yang tidak dibolehkan adalah menjatuhkan tuduhan
kepada seseorang tanpa bukti yang qath‘i atau zhanni.
Tuduhan yang dialamatkan oleh Kiai Noor dan beberapa
masyarakat terhadap perilaku berdakwah Kiai Dahlan jelas-jelas
tidak terbukti. Kiai Noor mendasarkan pada desas-desus yang
terjadi di masyarakat. Sebagai seorang kiai sebaiknya ia
93
memastikan terlebih dahulu perilaku yang dianggapnya
menyimpang dari ajaran Islam.
3) Dalam Menyampaikan Dakwah Perlu Mengetahui Sasarannya
Berdakwah adalah aktivitas ibadah. Dalam berdakwah ada
metode-metode yang harus dilalui agar dakwah tersebut diterima
oleh masyarakat sasarannya. Salah satu metodenya adalah agar
berdakwah mempertimbangkan kadar pengetahuan sasarannya.
“…Dengan mengetahui cara berpikir masyarakat tempatkita berada, maka akan lebih mudah bagi kita dalamberdakwah. Pengertian Kala Bendu ini mungkin saja takdimengerti masyarakat yang tinggal di Pulau Sumatera.”(Sang Pencerah, 2010:81).
4) Saling Membantu Ketika Saudara Kesusahan
Di antara kita terkadang terdapat masyarakat yang ditimpa
kesusahan. Tidak sedikit orang yang peduli terhadap sesama. Islam
sangat menekankan bahu-membahu di antara sesama umat Islam di
dalam menghadapi kesulitan.
“Ini juga uangku untukmu Dahlan,” sambung Kiai Ibrahimtiba-tiba. “Jumlahnya tidak banyak tapi untukmenengkanmu bahwa keluarga selalu mendukungmu”(Sang Pencerah, 2010:263).
Sebagai makhluk sosial, manusia tak dapat hidup sendirian,
walaupun telah memiliki segalanya seperti harta benda yang
berlimpah. Apabila hidup sendirian tanpa orang lain yang
menemani, tentu ia kesepian pula. Kebahagiaan pun mungkin tidak
pernah ia rasakan. Oleh karena itu, Islam menyuruh umat manusia
94
khususnya, bagi orang mukmin, untuk tolong-menolong
sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah, ayat 2 berikut ini:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orangyang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dankeredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikanibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kalikebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolongdalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamukepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
Melalui ayat tersebut di atas, Allah Swt. memerintahkan
umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam
mengerjakan kabaikan/kebajikan dan ketakwaan. Sebaliknya Allah
melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan
dosa dan pelanggaran.
95
f. Hubungan antarunsur dalam cerita
Hubungan antarunsur novel merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antarunsur
dalam novel Sang Pencerah dibahas satu per satu, yaitu judul dengan
tokoh, judul dengan alur, judul dengan latar, tokoh dengan alur, tokoh
dengan latar, tema dengan latar, tema dengan alur.
1. Hubungan Judul dengan Tokoh
Seperti yang telah diketahui bahwa judul berhubungan
dengan keseluruhan cerita, salah satunya dapat diekspresikan
dengan tokoh cerita, yang berupa nama tokoh, sikap tokoh, dan
watak tokoh. Judul Sang Pencerah dideskripsikan dengan tokoh
cerita dengan menonjolkan sikap tokoh. Sikap Kiai Dahlan yang
selalu bertentangan dengan para Kiai di kampungnya karena Kiai
Dahlan ingin meluruskan ajaran agama Islam yang diyakininya
telah melenceng atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad
saw. walaupun beliau mendapat hinaan dan bahkan dianggap
sebagai Kiai kafir, beliau tetap memperjuangkannya.
2. Hubungan Judul dengan Alur
Judul Sang Pencerah mempunyai arti orang yang telah
memberi pencerahan di dalam kehidupan dan alur dalam novel
Sang Pencerah ini maju. Dalam hubungan judul dengan alur
tersebut terlihat saat Kiai Dahlan menceritakan tentang
kelahirannya yaitu yang berbunyi
96
“Aku lahir pada 1868, atau 10 tahun lalu, ketika masyarakatYogyakarta masih belum lupa pada lindu yang mengoyakwilayah mereka setahun sebelumnya. Konon menurut bapak,beberapa orang tua yang biasa menafsirkan gejala alammenyampaikan kepadanya bahwa kelahiranku yang terjadisetelah gempa besar itu berarti bahwa aku, MuhammadDarwis, memang ditakdirkan untuk membawa perubahanbesar, kebangkitan kembali, atau menyusun sisa-sisabongkahan yang telah lama bersarang dibenak masyarakatdan dianggap sebagai keharusan yang tak perlu ditanyakanlagi” (Sang Pencerah, 2010: 12).
Dari penggalan kutipan ini dapat diketahui bahwa Kiai
Ahmad Dahlan berperan sebagai Sang Pencerah.
3. Hubungan Judul dengan Latar
Judul Sang Pencerah mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan latar. Semua itu diketahui dari pemilihan judul Sang
Pencerah dan latar yang disini disebutkan bahwa latarnya adalah
kehidupan masyarakat Jawa yang hidup di wilayah Kasultanan
Yogyakarta Hadiningrat, dalam segi sosial papan atas, sebutan Kiai
Dahlan adalah Sang Pencerah karena kehidupan beliau berinteraksi
langsung dengan lingkungan Keraton sehingga beliau tahu segala
aktivitas. Keraton yang dinilainya mengandung syirik dan bidah,
hingga akhirnya beliau meluruskan kembali, membersihkan ajaran
Islam dari bidah dan syirik walaupun banyak orang yang tidak suka
kepadanya.
4. Hubungan Tema dengan Latar
Seperti dijelaskan di atas, tema novel ini adalah perjuangan
Kiai Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam dari bidah dan
97
perjuangan mendirikan Muhammadiyah. Jika dilihat dari kata
“perjuangan” sudah tentu identik dengan usaha memperjuangkan
berdirinya Perserikatan Muhammadiyah. Latar tempat dalam
novel Sang Pencerah yaitu di lingkungan Keraton dimana
perjuangan Kiai Dahlan begitu sulit dalam mendirikan
Muhammadiyah karena lingkungan Keraton itu sendiri tradisi-
tradisi nenek moyang masih melekat.
5. Hubungan Tokoh dengan Alur
Dalam novel Sang Pencerah, hubungan antara alur dengan
tokoh dan penokohan dapat dilihat secara jelas. Tokoh Darwis
yang menyatakan pendapatnya tentang upacara Nyadran dibuat
sederhana saja, sehingga menimbulkan semua orang memusatkan
pandangan ke arah Darwis termasuk Kiai Penghulu dan Kiai Abu
Bakar. Oleh karena itu, terjadi perdebatan di antara para Kiai dan
anggota keluarga Darwis. Sesampainya di rumah, Kiai Abu Bakar
melontarkan kemarahannya kepada Darwis yang tidak tersalurkan
di Masjid Gedhe.
Hubungan alur dengan tokoh dapat dilihat pula ketika Kiai
Dahlan datang untuk pertama kalinya memberikan khutbah Jumat.
Ketika itu, beliau secara tegas menolak tradisi-tradisi yang ada di
masyarakat sehinggga membuat Kiai Penghulu memberikan
teguran kepada Kiai Dahlan lewat Kiai Noor yang juga kakak ipar
Kiai Dahlan, dan setelah Kiai Penghulu menyuruh Kiai Dahlan
98
untuk menutup Langgar Kidul, tetapi Kiai Dahlan tidak mau
menuruti keinginan Kiai Penghulu hingga terjadi penghancuran
Langgar Kidul oleh orang suruhan Kiai Penghulu. Sejak saat itu
hubungan Kiai Dahlan dengan para Kiai di Kauman kurang baik.
Hubungan alur dengan tokoh juga terlihat, saat Kiai Dahlan
berdamai dengan Kiai Penghulu. Kiai Penghulu akhirnya meminta
maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah beliau lakukan kepada
Kiai Dahlan, terutama saat Kiai Penghulu berburuk sangka bahwa
Kiai Dahlan akan merebut posisinya sebagai Kiai Penghulu di
masjid Gede Kauman.
6. Hubungan Tokoh dan Penokohan dengan Latar
Tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita memerlukan ruang dan
keadaan sosial tempat mereka melakukan atau melakukan sesuatu.
Ruang dan keadaan tersebut berpengaruh pula terhadap tokoh dan
penokohan.
Tokoh-tokoh dalam novel Sang Pencerah adalah masyarakat
daerah Jawa, yaitu tepatnya di Yoyakarta. Selain itu pola pikir para
tokoh juga sederhana kecuali Kiai Ahmad Dahlan. Walaupun Kiai
merupakan keturunan priyayi Jawa, beliau banyak mempelajari
ilmu dari orang-orang yang pintar seperti, Syaikh Rasyid Ridha,
Syaikh Jambak dan Syaikh Khabib Al-Mangkabawi. Kiai Dahlan
sejak kecil sudah memiliki kecerdasan yang tinggi dibandingkan
99
anak-anak seusianya, terbukti saat usia delapan tahun, beliau sudah
khatam Alquran dan lancar berbahasa arab.
7. Hubungan Alur dengan Latar
Alur merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab
akibat di dalam cerita, sedangkan latar adalah tempat, saat, dan
keadaan sosial yang menjadi tokoh melakukan dan dikenai
kejadian.
Novel Sang Pencerah seperti yang sudah disebutkan
sebelumnya menampilkan cerita yang berlatar belakang priyayi
Jawa yang hidup di wilayah Keraton. Dalam novel tersebut
dilukiskan mulai dari tempat tinggal kehidupan sampai pada adat
istiadat yang dianut. Latar tempat kebanyakan berada di sekitar
Kauman Yogyakarta dan masyarakatnya masih banyak menganut
tradisi nenek moyang seperti tradisi yasinan, nyadran, ruwatan dan
padusan.
Berawal dari yasinan 40 hari meninggalnya bapak Pono,
hingga acara pertemuan Takmir yang membahas tentang upacara
nyadran, sejak saat itu konflik mulai muncul antara Kiai Dahlan
dengan Kiai Penghulu. Kiai Dahlan kemudian menunaikan ibadah
haji ke Mekkah selama lima tahun. Setelah itu, beliau kembali ke
Jawa. Konflik antara Kiai Dahlan dan Kiai Penghulu muncul
kembali setelah Kiai Dahlan mengungkapkan bahwa arah kiblat
Masjid Gedhe salah. Selain Masjid Gedhe Kauman, kebanyakan
100
arah kiblat Masjid di daerah Jawa juga tidak tepat karena Kiai
Dahlan telah membuktikan sendiri dengan mengunjungi tempat
lain seperti masjid daerah Magelang. Semenjak saat itu, Kiai
Dahlan membicarakan tentang masalah arah kiblat Masjid Gedhe
dengan para Kiai di Kauman.
8. Hubungan Tema dengan Alur
Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang hendak
disampaikan pengarang kepada pembaca. Untuk menyampaikan
ide atau gagasan pengarang menciptakan cerita yang terdiri dari
berbagai peristiwa yang terjalin dalam hubungan sebab-akibat
(plot). Adanya peristiwa sebab-akibat tersebut bersifat mutlak
supaya cerita lebih jelas dan tema dapat ditemukan. Sebaliknya,
untuk menentukan tema dapat dilihat melalui konflik-konflik yang
menonjol yang termasuk bagian dari plot.
Tema novel Sang Pencerah adalah perjuangan memurnikan
ajaran Islam dari unsur bidah dan perjuangan mendirikan
Muhammadiyah sebagai wadah organisasinya. Untuk membawa
tema ini, pengarang membuat cerita mengenai seseorang yang
mempunyai sifat pemaaf, dan tidak pendendam. Dari hal tesebut
muncul masalah-masalah yang membuat cerita terus bergerak
dalam novel Sang Pencerah.
Konflik dalam novel Sang Pencerah berawal dari usulan Kiai
Dahlan mengenai upacara nyadran, pendapatnya yang saat itu
101
membuat perdebatan di antara anggota keluarganya yang
mengakibatkan konflik berlanjut yakni saat Kiai Dahlan
mengungkapkan bahwa arah kiblat Masjid Gedhe salah. Selain itu
beliau berpakaian dan mendirikan sekolah yang dituding sebagai
Kyai Kafir karena mirip dengan orang kafir.
9. Hubungan Tema dengan Tokoh dan Penokohan
Untuk menyampaikan ide atau gagasan utama, diperlukan
pembawa gagasan untuk berupa pelaku atau tokoh-tokoh cerita.
Biasanya pembawa gagasan utama adalah tokoh-tokoh utama,
sementara tokoh lain merupakan tokoh latar yang memperkuat
penokohan tokoh utama dan gagasan yang dibawanya.
Tema dalam novel Sang Pencerah adalah perjuangan
memurnikan ajaran Islam dari unsur bidah. Dari tema tersebut, Kiai
Dahlan digambarkan sebagai orang yang tegar dan tidak mudah
putus asa memurnikan ajaran Islam dari bidah dan syirik.
Perjuangan Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah begitu
sulit dan banyak sekali cobaan yang dhadapinya hingga dituduh
sebagai kiai kafir. Namun, beliau tetap memperjuangkannya hingga
berdirinya Muhammadiyah yang mempunyai arti orang-orang yang
mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw.
2. Nilai-Nilai Religius dalam Novel Sang Pencerah
Berdasarkan penyajian data di atas, pembahasan nilai religius
khususnya nilai-nilai Islam dalam novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral sebagai berikut:
102
a. Hubungan Manusia dengan Tuhan
Hubungan manusia dengan Tuhannya adalah hubungan vertikal
yang menghubungkan perasaan manusia dengan Tuhannya, Allah Swt.
Memelihara hubungan dengan Allah Swt. secara terus-menerus
menjadi kendali diri kita sehingga dapat terhindar dari kejahatan dan
kemungkaran. Wujud keterikatan batin manusia dengan Tuhannya
dimulai dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi
segala larangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
1) Setiap Muslim Wajib Melaksanakan Salat Lima Waktu Sehari
Salat merupakan perintah wajib kedua bagi umat Islam, baik
laki-laki maupun wanita yang telah memenuhi persyaratan. Salat
diwajibkan kepada setiap kaum muslimin dan tidak boleh
meninggalkannya kecuali bagi orang gila, anak yang belum baligh,
dan wanita yang sedang haid atau nifas. Kewajiban salat tersebut
didasarkan pada dalil-dalil dalam bentuk perintah yang terdapat
dalam Alquran dan Hadis Nabi. Di antara dalil-dalil tersebut adalah
QS Al-Baqarah ayat 43, yaitu
�˴Ϧ˸ϴ˶ό˶ϛήϟ�˴ϊ ϣ˴˸Ϯό˵ϛ˴έ˸˴ϭ˴ΓϮϛ˴ΰϟ�˸ϮΗ˵˴ϭ�˴Δԩ˴Ϡμ ϟ�˸ϮϤ˵˸ϴ˶ϗ˴˴ϭ
Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah
beserta orang-orang yang rukuk.
Ayat Alquran ini secara jelas memerintahkan setiap muslim
untuk melaksanakan salat. Tentunya salat yang dimaksud adalah
salat yang wajib (far-du).
103
Dalam novel Sang Pencerah terlihat, Kiai Dahlan mengikuti
salat berjamaah di Masjid Gedhe Kauman. Berikut ini kutipan
adegan tersebut.
Salat subuh berjamaah akan dimulai diimami oleh KiaiAbdullah Siraj Pakualaman (Sang Pencerah, 2010: 212).
2) Tawakkal kepada Allah
Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang Islam adalah
berserah kepada Allah (tawakal). Sifat berserah tersebut
menandakan derajat ketakwaaan seseorang kepada Allah. Dalam
novel Sang Pencerah sifat penyerahan tersebut misalnya terlihat
dalam peristiwa kematian ibu Kiai Dahlan.
“Namun, Allah juga punya rencana lain bagiku. Ditipkan-Nya bagiku tambahan satu nyawa dan diambil-Nya satunyawa pada tahun yang sama. Penyakit ibu yang sedangmenahun akhirnya tak bisa tersembuhkan. Kematian ibudisambut kedukaan yang sangat besar oleh warga Kaumankarena sifat social beliau yang tinggi semasa hidup.”(SangPencerah, 2010:161).
Perintah untuk berserah diri kepada Allah ditegaskan di dalam
QS Ali Imran ayat 122 sebagai berikut:
Artinya :
“Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena
takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu.
104
Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin
bertawakkal.” (QS Ali Imran, ayat 122)
Perintah Tawakal terdapat juga dalam QS al-Ahzab, ayat 3
“dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai
Pemelihara” (QS al-Ahzab : 3).
3) Sifat Syukur kepada Allah
Pada dasarnya semua yang diterima oleh manusia adalah
pemberian Allah. Oleh karena itu, manusia harus mensyukuri setiap
pemberian tersebut. Dalam novel tersebut pesan untuk bersyukur
misalnya terdapat pada kutipan berikut:
“Ini rezeki dari Gusti Allah, bukan dari saya,” ujarku.“Sering-seringlah berterima kasih kepada Allah.” (SangPencerah, 2010:91).
Di dalam Alquran, kata syukur dengan kata nikmat
disejajarkan oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah patut kita
syukuri sesuai dengan kemampuan kita.
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat
(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu
mengingkari (nikmat)-Ku” (QS Al-Baqarah:152).
Dijelaskan juga dalam Alquran dalam surat Ibrahim ayat 7 :
105
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
4) Sifat Jujur ketika Berdagang
Berdagang merupakan aktivitas mencari rezeki. Adakalanya
orang berdagang hanya untuk mendapatkan keuntungan materi.
Namun, berbeda dengan yang ditampilkan di dalam novel Sang
Pencerah, di mana dalam berdagang seseorang tidak boleh hanya
mengambil keuntungan semata, tetapi harus memikirkan ibadah.
“Kiai Haji Muhammad Fadil itu pedagang yangbertanggungjawab, Bu. Beliau tidak mau menjual barangyang jelek semata-mata untuk mengejar keuntunganduniawi. Buat beliau berdagang itu adalah ibadah.” (SangPencerah, 2010:46).
Mengenai masalah perdagangan ini, Alquran menyebutkan
bahwa berlaku adil itu merupakan sesuatu yang penting di dalam
beragama. Allah membenci orang yang tidak berlaku adil di dalam
segala aktivitasnya. Berlaku adil juga berlaku di dalam berdagang.
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadiorang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karenaAllah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kalikebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamuuntuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itulebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
106
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan” (QS Al-Maidah ayat 8).
5) Pemimpin yang Bertanggung Jawab
Tugas pemimpin merupakan tugas mulia yang menuntut
kerja keras dan pertanggungjawaban. Pemimpin bertanggung
jawab kepada sesama manusia dan Allah. Hal tersebut terlihat jelas
di dalam petikan novel berikut ini:
“Berdirinya masjid di besar di dekat keraton menampilkanpesan yang sangat jelas bahwa Sri SultanHamengkubuwono I, dan para keturunannya kelak, bukansemata-mata berfungsi sebagai Senopati ing Ngalogo(pimpinan pemerintahan dan perang), melainkan jugasebagai Sayyidin Panatagama Khalifatullah alias wakilAllah Swt, di dunia dalam memimpin pelaksanaan agama”(Sang Pencerah, 2010:8).
Mengenai kepemimpinan di dalam salah satu hadis
disebutkan sebagai berikut
حديث عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما. ان رسول اهللا
اهللا عليه وسلم قال : كللكم راع مسول عن ر عيته صلى
واال مري الذي على الناس راع و هو مسول عنهم.Hadis Riwayat Umar bin Abdullah, Rasulullah bersabda
“setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung
jawab terhadap yang dipimpinnya”.
6) Islam adalah Agama yang Membawa Rahmat
Salah satu risalah di dalam Islam adalah bahwa Islam
adalah agama rahmat. Rahmat berarti memberi perlindungan
kepada semua kalangan. Islam diharapkan menjadi solusi terhadap
107
persoalan dunia. Dalam Novel Sang Pencerah ini disebutkan
sebagai berikut:
“Allah Swt., berfirman bahwa Islam adalah rahmatan lil‘alamin, rahmat bagi seluruh alams emesta,” ujarkumembuka khutbah. “Islam harus menjadi rahmat bagi siapasaja yang bernaung di dalamnya, baik Muslim maupunBukan Muslim.” (Sang Pencerah, 2010:175).
7) Tidak Boleh Taklid dalam Beragama
Persoalan taklid telah menjadi perbincangan sepanjang
masa. Taklid adalah mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui
pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan Alquran dan
hadis. Silang pendapat mengenai taklid jugalah yang menjadi
sorotan di dalam novel ini, seperti kutipan berikut:
“Oh, jangan salah, Kiai Dahlan. Kepatuhan berlebihan padatradisi ini, taklid yang menggerogoti umat ini, sudahmenjadi penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi karenabanyak kiai yang diuntungkan dari taklid-taklid inisehingga mereka bukannya membantu menjernihkan akidahumat, malah ikut melestarikan kebiasaan-kebiasaan itu”(Sang Pencerah, 2010: 257).
Menurut Darwis, tradisi padusan dan ruwatan yang
dilakukan masyarakat saat memasuki bulan Ramadhan bukan
merupakan suatu kewajiban. Puasalah yang seharusnya dilakukan
masyarakat.
“Misalnya seperti padusan dan ruwatan memasukiramadhan itu. Banyak masyarakat yang menyangka wajibhukumnya melakukan padusan dan ruwatan, sementarapada saat bulan suci sekarang sendiri kalian lihat sendiri dipasar banyak yang tidak puasa. Padahal justru puasa ituyang wajib dilakukan, bukan padusan, kata Darwis” (SangPencerah, 2010: 98).
108
Di dalam QS At-Taubah : 31 disebutkan bahwa praktik
taklid telah terjadi sepanjang masa, dan hal itu dilarang oleh
agama.
والمسیح ابن اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون هللا
مریم وما أمروا إال لیعبدوا إلھا واحدا ال إلھ إال ھو سبحانھ
ا یشركون عم
Artinya:
“Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib merekasebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) AlMasih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembahTuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”(QS At Taubah: 31).
b. Hubungan Manusia dengan Manusia
Manusia tidak dapat lepas dari kehidupan sosial karena kehidupan
tidak akan terjadi tanpa ada orang lain. Maksudnya seseorang tidak
mungkin hidup tanpa ada bantuan orang lain. Contohnya orang kaya
yang mempekerjakan orang yang kurang mampu untuk merawat
kebunnya. Dalam hal ini, terjadi hubungan saling membantu antara si
kaya dan si miskin karena keduanya saling menguntungkan. Orang
kaya mendapatkan jasa si miskin merawat kebun miliknya, sedangkan
si miskin memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya
dari merawat kebun milik orang kaya.
Hubungan antara manusia dengan manusia dalam novel Sang
Pencerah tampak dalam beberapa kutipan sebagai berikut:
109
1. Hubungan yang baik antara Darwis dengan Bapaknya dan Ibunya
Darwis dilahirkan dari pasangan Siti Aminah dan Kiai Abu
Bakar. Siti Aminah sendiri adalah anak dari kiai besar, yaitu Kiai
Ibrahim, sedangkan Kiai Abu Bakar adalah imam dan khatib
Masjid Gedhe. Seperti kutipan berikut ini:
“Bapak menikah dengan ibuku, Siti Aminah putrid Kiaihaji Ibrahim, seorang penghulu Kasultanan yang cukupterpandang. Pernikahan itu menghasilkan tujuan oranganak,…anak lelaki yang berada di posisi keempat itu diberinama Muhammad Darwis, namaku” (Sang Pencerah,2010:11.
Sosok Darwis sangat dipengaruhi oleh sosok ayahnya yang
seorang imam dan khatib Masjid Gedhe. Ia banyak bertukar fikiran
mengenai berbagai hal, terutama mengenai kegelisahan-
kegelisahannya.
“Di mana Afrika itu, Bapak?, apakah masih di dekat Gresikjuga?”“Afrika itu jauh sekali dari sini. Bapak dengar masih lebihjauh dari Makkah. Paahal untuk ke Makkah saja butuhwaktu berbulan-bulan perjalanan dengan kapal laut” (SangPencerah, 2010:14).
2. Membangun Pertemanan
Darwis dan Pono merupakan dua orang teman yang
memiliki minat yang tinggi dalam belajar Islam dan/atau mengaji.
Pertemanan itu terjadi hingga Darwis berangkat menuntut ilmu ke
Makkah. Kutipan berikut menunjukkan kedekatan hubungan
keduanya sebagai teman kecil.
“Darwis, jangan lupa nanti malam yasinan di rumahku,”seru Pono dari jauh sambil mengacungkan tangannya. Aku
110
balas mengacungkan tangan sbagai tanda “ya”. (SangPencerah, 2010:24)
Selain dengan Pono selaku teman dekat, Darwis juga
menjalin hubungan dengan teman-teman lainnya seperti dengan
teman-temannya dari Kauman yang biasa bermain bola bersama.
“Aku dan kawan-kawan dari kauman sedang bermain bolamelawan anak-anak Ngadisuryan di Alun-Alun Selatan.Matahari yang mulai rebah kea rah Barat membuat cuacatak terlalu panas memanggang” (Sang Pencerah, 2010: 49).
3. Menghormati guru
Guru adalah orang yang mengarahkan dan mendidik kita
berbagai hal. Ketika orang tua tidak sempat atau tidak mampu
untuk mengajarkan tentang berbagai ilmu, terutama soal akidah
guru memegang peranan penting dalam mengajar dan mendidik
anak. Oleh karena itu, seorang murid harus menghormati guru.
“Salah seorang Ulama yang sangat aku hormati adalah KiaiAbdul Hamid Lempuyangan. Beliau orang yang berilmutinggi dan sangat sederhana seperti lazimnya para kiai.Beliau punya satu kebiasaan yang menonjol rasa kasihsayang yang luar biasa terhadap anak-anak yatim piatu.”(Sang Pencerah, 2010:63)
Diriwatkan oleh at-thabarani dan al-Hakim kewajiban
untuk menghormati guru.
“Bukan umat-Ku siapa yang tidak memuliakan orang yanglebih tua, tidak kasihan kepada orang yang lebih muda dantidak menunaikan hak guru”.
Hadis lain yang mewajibkan kita untuk menghormati guru
adalah Hadis yang diriwayatkan oleh at-Thabarani.
111
“belajarlah ilmu, belajarlah ilmu untuk ilmu dan tundukpatuhlah kepada orang yang kamu belajar ilmu darimereka” (HR at-Thabarani).
4. Menyantuni Anak Yatim Piatu
Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah dan
ibunya. Islam memberikan kedudukan istimewa bagi anak yatim
serta orang yang berderma terhadap mereka. Perilaku yang
ditunjukkan oleh tokoh Kiai Hamid adalah perilaku terpuji yang
memang dianjurkan oleh Islam.
“Susah dijelaskan dengan akal pikiran biasa Wis,”kataBapak. Tapi jika di hatimu selalu timbul keinginan untukmembantu orang, meringankan beban orang, Allah akanselalu mengalirkan rezeki kepada orang yang selalumembantu makhluk Allah lainnya”(Sang Pencerah,2010:65).
Dalam surat Ad Dhuha ayat 9 dijelaskan tentang kewajiban
menyantuni anak yatim :
“Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-
wenang” (QS Ad Dhuha: 9).
5. Menikah Jika Cukup Umur
Perintah menikah merupakan perintah sunnah. Menikah
dilakukan ketika sudah mencapai usia yang cukup matang. Pada
tahun 1889, Darwis dan Walidah menikah dalam suasana penuh
kebahagiaan. Pernikahan itu terjadi ketika Darwis berusia 21 tahun,
sedangkan Walidah berusia 17 tahun. Suatu usia yang cukup untuk
menjalani hidup di dalam suatu ikatan perkawinan.
112
“Kalender Masehi yang digunakan Pemerintah HindiaBelanda menunjukkan tahun 1889 ketika Sunnah Nabiuntuk membentuk keluarga bagi setiap Muslim itu akhirnyaaku jalankan…” (Sang Pencerah, 2010: 156).
c. Hubungan Manusia dengan Alam
Manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia diwajibkan
hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya seperti
pohon-pohon. Tidak ada kekuatan selain Allah. Bagi manusia pohon
dapat dijadikan media untuk kebutuhan manusia dalam membangun
rumah. Pohon tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk memberikan
keuntungan bagi manusia. Pohon tidak boleh disembah dan dimintai
sesuatu pertolongan dan atau keberuntungan seperti dilakukan oleh
suami-isteri dalam kutipan berikut ini:
“Pulang dari Masjid Gedhe, aku melihat sepasang suami-isterimemberikan sesaji dan membakar kemenyan di antara pohonberingin dengan sangat hati-hati.”“Aku dekati pohon beringin itu dengna berjalan sewajarmungkin, sebelum mengendap-ngendap dan dengan cepatmengambil sesajan dan kembali bertingkah sewajar mungkinseperti sebelumnya” (Sang Pencerah, 2010: 90).
3. Skenario Pembelajaran Unsur Intrinsik dan Nilai Religius Novel Sang
Pencerah Karya Akmal Nasery Basral di kelas XI SMA
Dalam pembelajaran sastra seorang guru tidak hanya mengajarkan
teori-teori saja. Seorang guru harus mengenalkan karya sastra dan
menerapkan teori-teori tersebut untuk mengapresiasi karya sastra. Dengan
mengapresiasi karya sastra dapat melatih siswa mempertajam perasaan,
penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya,
113
agama, dan lingkungan hidup. Pengalaman siswa dalam mengkaji dan
mengapresiasi karya sastra (khususnya sastra Islami) berdampak positif
dan berpengaruh terhadap kepekaan, religi, dan nalar siswa. Misalnya
nilai-nilai positif dalam karya sastra seperti yang dicontohkan dalam novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral seperti tidak boleh dendam
kepada sesama muslim dan saling memaafkan.
Penulis memperhatikan tingkat penguasaan bahasa siswa sehingga
dalam menyampaikan materi tidak mengalami kesulitan. Pada novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral, bahasa yang digunakan adalah
bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa dalam novel ini
dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam berbahasa, setidaknya siswa
berusaha untuk memahami bahasa lain, tidak hanya bahasa Indonesia. Hal
tersebut dapat menambah ragam bahasa siswa.
a. Tujuan Pembelajaran Unsur Intrinsik dan Nilai Religius Novel
Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral.
Tujuan pembelajaran sastra secara umum di SMA adalah peserta
didik mampu menikmati, menghayati, memahami dan memanfaatkan
karya sastra untuk pengembangan kepribadian, memperluas wawasan
kehidupan dan kemampuan berbahasa.
1) Standar Kompetensi
Standar kompetensi dalam pembelajaran sastra adalah
memahami novel Indonesia atau novel terjemahan.
114
2) Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar dalam pembelajaran novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral adalah menganalisis unsur
ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik yang dibahas adalah nilai
religius dalam novel Sang Pencerah.
3) Indikator Hasil Belajar
Indikator hasil belajar untuk mengajarkan nilai religius
sastra di SMA, yaitu:
(a) Siswa mampu menceritakan isi novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral.
(b) Siswa dapat menemukan nilai religius dalam novel Sang
Pencerah.
(c) Siswa dapat menjelaskan nilai religius dalam novel Sang
Pencerah.
b. Strategi Pembelajaran Unsur Intrinsik dan Nilai Religius Novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi sastra
yang meliputi tiga tahap, yaitu:
1) Tahap penjelajahan
Tahap penjelajahan merupakan tahap awal yang dilakukan
dalam strategi sastra. Kegiatan tahap ini memberikan kesempatan
pada peserta didik untuk mengapresiasi karya sastra.
Langkah-langkah yang dilakukan :
115
(a) Guru mengucapkan salam.
(b) Guru menyampaikan materi tentang unsur intrinsik dan nilai
religius.
(c) Siswa diminta untuk membaca novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral dan mendata unsur intrinsik serta nilai
religius yang ditentukan.
2) Tahap Interpretasi
Tahap interpretasi merupakan kegiatan mendiskusikan
materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik serta mendiskusikan
novel yang telah dibaca.
Langkah-langkah yang dilakukan :
(a) Guru menjelaskan tentang novel, unsur intrinsik dan unsur
ekstrinsik novel.
(b) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Setiap
kelompok terdiri dari 5 siswa.
(c) Guru membagi siswa dalam kelompoknya. Materi yang
didiskusikan yaitu mendiskusikan struktur (unsur intrinsik dan
ekstrinsik) terutama nilai-nilai religius yang terdapat dalam
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral.
(d) Guru memberi ulasan dan penjelasan yang berupa simpulan.
3) Tahap Rekreasi
Tahap rekreasi adalah kegiatan siswa untuk merekreasikan
kembali hal-hal yang diperolehnya menggunakan kata-kata sendiri.
116
Adapun kegiatan yang ditempuh yaitu siswa diminta untuk
menuliskan kembali tentang struktur dan nilai-nilai religius
menggunakan bahasa sendiri.
c. Bahan Pembelajaran Sastra
Pemilihan novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
sebagai bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas
XI SMA dapat dilihat dari segi antara lain (1) segi bahasa, (2) segi
psikologi, dan (3) segi latar belakang kebudayaan.
1) Segi bahasa
Novel sebagai bahan pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia di kelas XI SMA, hendaknya novel tersebut
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dari
segi bahasa, novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia, namun
sebagian kecil bahasa Arab dan bahasa Jawa. Bahasa Arab
digunakan untuk mempertegas nilai-nilai Islam yang ada dalam
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral, bahasa Jawa
digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan
budaya dan adat istiadat Jawa. Bahasa Arab digunakan untuk
mempertegas nilai-nilai agama Islam yang ada dalam novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral, penggunaan bahasa
Arab dan bahasa Jawa tidak mengurangi nilai sastra yang ada
dalam novel tersebut karena penggunaan masing-masing bahasa
117
adalah bahasa yang mudah dipahami dan sudah tidak asing lagi
didengar oleh umat Islam dan Warga Negara Indonesia.
Penggunaan bahasa Jawa seperti ajek, lindu, ndak, ngelindur,
dan keblinger, sedangkan penggunaan bahasa arab seperti
astaghfirullah, Alhamdulillah, thayyib, assalamu ‘alaikum, dan
hadas.
2) Segi Psikologi
Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
sebagai bahan pembelajaran sastra mengandung permasalahan
hidup dan persoalan nilai-nilai hidup. Siswa dapat dirangsang
untuk menemukan persoalan hidup dan mencari penyelesaian
tentang masalah kehidupan seperti yang terdapat dalam novel
misalnya K.H. Ahmad Dahlan saat langgar atau suraunya
dibakar oleh santri Kyai Kamaludiningrat. Saat itu K.H.Ahmad
Dahlan hanya bisa menangis menyaksikan kejadian itu bahkan
beliau hampir pergi dari Kauman. Namun, atas dukungan dan
pemberian uang dari kakak-kakaknya akhirnya langgar itu
kembali dibangun.
3) Segi Latar Belakang Budaya
Para siswa akan mudah tertarik pada karya-karya yang
ada hubungannya dengan budayanya sendiri. Seorang guru
hendaknya dapat memahami dan mengambil peluang dari
ketertarikan siswa tersebut dengan cara menyelidiki fasilitas
118
novel yang ada kaitannya dengan budaya siswanya. Dalam
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral mengisahkan
tentang seorang yang berlatar belakang budaya Jawa khususnya
dan Indonesia pada umumnya dan juga berlatar belakang orang
yang selalu patuh dengan ajaran agama Islam serta orang yang
teguh pendirian untuk menggapai sebuah keberhasilan sehingga
bermanfaat apabila diajarkan di SMA.
d. Skenario langkah-langkah Pembelajaran
Pembelajaran novel dengan materi nilai religius pada novel
Sang Pencerah berfokus pada aspek membaca. Sehubungan
dengan hal itu penulis memaparkan skenario pembelajaran berupa
RPP (Terlampir). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dibuat
berdasakan silabus. Di bawah ini disajikan langkah-langkah
pembelajaran novel dengan materi nilai religius pada novel Sang
Pencerah di kelas XI SMA.
a. Pertemuan pertama dengan alokasi waktu 2 x 45 menit.
1) Guru memberikan teori atau menerangkan tentang unsur
intrinsik novel dan nilai-nilai yang terdapat dalam karya
sastra dengan alokasi waktu 30 menit.
Guru pada tahap ini dapat menggunakan metode
ceramah untuk menyampaikan teori tentang unsur intrinsik
dan ektrinsik (nilai religius) yang terdapat pada karya
sastra. Metode ceramah dilakukan dengan penuturan secara
119
lisan oleh guru terhadap siswa yang pelaksanaannya dapat
dibantu dengan alat bantu mengajar untuk lebih
memperjelas materi yang disampaikan.
2) Guru mengajak siswa untuk membaca novel Sang
Pencerah dengan alokasi waktu 60 menit.
Membaca novel memerlukan waktu yang cukup
lama, oleh karena itu guru mengajak siswa untuk
melanjutkan membaca novel Sang Pencerah di luar jam
sekolah. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah
metode membaca. Metode tersebut menuntut siswa untuk
berkonsentrasi tinggi agar dapat menangkap isi dari novel
yang dibaca.
b. Pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 x 45 menit.
1) Guru menugaskan siswa untuk mengidentifikasi dan
menganalisis unsur intrinsik dan nilai religious yang
terdapat pada novel Sang Pencerah dengan alokasi waktu
40 menit.
Pada tahap ini siswa mendapatkan tugas dari guru
untuk mengidentifikasi serta menganalisis unsur intrinsik
dan nilai religius yang terdapat dalam novel Sang
Pencerah dengan metode analisis isi. Metode analisis isi
merupakan teknik penelitian dengan menguraikan isi dari
objek yang diteliti.
120
2) Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan unsur
intrinsik dan nilai religius pada novel Sang Pencerah
dengan alokasi waktu 30 menit.
Pada kegiatan diskusi ini metode yang digunakan
adalah metode diskusi dengan cara pengelompokan. Peserta
didik dibagi menjadi lima kelompok, kemudian masing-
masing kelompok mendiskusikan unsur intrinsik dan nilai
religius yang terdapat dalam novel Sang Pencerah. Dengan
kegiatan ini peserta didik tidak hanya berpegang pada hasil
pemikiran sendiri, juga dapat memberi dan menerima
masukan terhadap jawaban atau hasil pemikiran teman.
3) Siswa diminta untuk melaporkan hasil diskusi dengan
alokasi waktu 20 menit.
Pada tahap ini masing-masing kelompok menunjuk
seorang perwakilan untuk melaporkan hasil diskusinya di
depan kelas secara bergantian. Metode yang digunakan
pada tahap ini adalah metode presentasi atau membaca.
Setelah semua perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil diskusi mereka, guru memberi evaluasi secara singkat
agar siswa dapat mengetahui bagaimana perbaikan hasil
diskusi siswa.
Dari langkah-langkah pembelajaran di atas dapat dirumus-
kan skenario pembelajaran novel di kelas XI SMA dengan materi
121
religius pada novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
sebagai berikut.
a. Pertemuan pertama dengan olokasi waktu 2 x 45 menit.
1) Pendahuluan dengan alokasi waktu 5 menit.
a) Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk
berdoa.
Guru : “Assalamu’allaikum warahmatullahi
wabarakatuh.”
Siswa : “Wa’alaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.”
Guru : “Selamat pagi/siang anak-anak!”
Siswa : “Pagi/siang, Bu!”
Guru : “Baiklah anak-anak sebelum kita
melaksanakan kegiatan belajar hari
ini, marilah kita awali dengan
membaca Basmalah bersama-sama.”
Siswa dan Guru : “Bismillahirrah manirrahim.”
b) Guru mengecek kehadiran siswa.
Guru : “Apakah ada teman Anda yang tidak
masuk hari ini?”
(Guru sambil membuka buku presensi kehadiran siswa
yang ada di meja guru juga menanyakan atau
122
mengkonfirmasi kepada siswa mengenai kehadiran
teman mereka).
Siswa : Ada, Bu/tidak ada, Bu.
2) Kegiatan inti dengan alokasi waktu 80 menit.
a) Guru menyampaikan materi mengenai unsur intrinsik
dan ekstrinsik (nilai religius) dalam karya sastra.
Pada tahap ini guru menggunakan metode
ceramah untuk menyampaikan teori tentang unsur
intrinsik dan ekstrinsik (nilai religius) yang terdapat
dalam karya sastra.
Guru : “Anak-anak pelajaran kita hari ini adalah
pembelajaran novel. Ibu akan
menyampaikan materi tentang unsur
intrinsik dan ekstrinsik (nilai religius)
pada novel (karya sastra).”
b. Guru mengajak siswa untuk membaca novel Sang Pencerah
dengan alokasi waktu 60 menit.
Guru : “Karena tadi kita sudah mempelajari teori-teori tentang
unsur intrinsik dan ekstrinsik (nilai religius) pada karya
sastra. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita
pelajari tersebut marilah kita membaca novel Sang
Pencerah Cermatilah unsur intrinsik dan ekstrinsik (nilai
religius) yang terdapat dalam novel tersebut!”
123
3) Penutup dengan alokasi waktu 5 menit.
Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam.
Guru : “Baiklah anak-anak berhubung waktunya sudah habis
membaca novelnya sampai di sini saja. Bagian novel yang
belum sempat dibaca kita lanjutkan nanti sepulang
sekolah. Untuk itu, dimohon sepulang sekolah nanti anak-
anak semua untuk tidak pulang terlebih dahulu. Terima
kasih perhatiannya, jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”
Siswa : “Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.”
b. Pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 x 45 menit.
1) Pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit.
a) Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa.
Guru : “Assalamu’allaikum warahmatullahi
wabarakatuh.”
Siswa : “Wa’alaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.”
Guru : “Selamat pagi/siang anak-anak!”
Siswa : “Pagi/siang, Bu/Pak!”
Guru : “Baiklah anak-anak sebelum kita
melaksanakan kegiatan belajar hari ini,
marilah kita awali dengan membaca Basmalah
bersama-sama.”
Guru dan Siswa: “Bismillahirrahmanirrahim.”
124
b) Guru mengecek kehadiran peserta.
Guru : “Apakah ada teman Anda yang tidak masuk
hari ini?”
(Guru sambil membuka buku absensi kehadiran siswa yang ada
di meja guru juga menanyakan atau mengkonfirmasi kepada
siswa mengenai kehadiran teman mereka).
c) Guru mengulas kembali materi sebelumnya.
Guru sedikit mengulas materi sebelumnya dengan tujuan
mengingatkan kembali siswa tentang materi yang telah
dipelajari.
Guru : “Anak-anak pada pertemuan kemarin kita
telah mempelajari materi unsur intrinsik dan
ekstrinsik (nilai religius) pada karya sastra dan
kita juga telah membaca novel Sang Pencerah.
Apakah kalian masih ingat apakah yang
disebut dengan tema?”
Siswa : “Tema adalah gagasan sentral yang menjadi
ide pokok dalam suatu karya sastra.”
Guru : “Berdasarkan fungsinya tokoh dibedakan
menjadi dua, yaitu? ”
Siswa : “tokoh sentral dan tokoh bawahan”
Guru : “Siapakah tokoh sentral atau utama dalam
novel Sang Pencerah tersebut?”
Siswa : “ K.H. Ahmad Dahlan.”
125
2) Kegiatan inti dengan alokasi waktu 75 menit.
a) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengidentifikasi
dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik (nilai religius)
novel Sang Pencerah dengan alokasi waktu 30 menit.
Guru : “Sekarang silakan Anda mengidentifikasi dan
menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik
(nilai religius) pada novel Sang Pencerah yang
telah Anda baca bersama kemarin. Ibu berikan
waktu 30 menit dari sekarang.”
b) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk
mendiskusikan hasil pekerjaan mereka, yaitu mengidentifikasi
dan menganalisis unsur intrinsik dan nilai religius novel Sang
Pencerah dengan alokasi waktu 25 menit.
Pada kegiatan ini metode yang digunakan adalah metode
diskusi. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok kemudian, masing-
masing kelompok diminta untuk mendiskusikan unsur intrinsik
dan nilai religius yang terdapat dalam novel Sang Pencerah.
Guru : “Anak-anak sekarang saya minta kalian
membentuk kelompok. Karena jumlah siswa di
kelas ini berjumlah 30 orang, bagilah menjadi
5 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 6
orang.”
Siswa berdiskusi dan mencocokkan hasil pekerjaan
mereka masing-masing kepada teman satu kelompok. Dengan
126
adanya kegiatan ini siswa tidak hanya berpegang pada hasil
pemikiran sendiri. Namun, juga dapat memberi dan menerima
masukan terhadap jawaban atau hasil pemikiran orang lain.
c) Guru memberi tugas siswa untuk mempresentasikan hasil
pekerjaan melalui perwakilan kelompok dengan alokasi waktu
20 menit.
Pada tahap ini guru member tugas setiap kelompok
menunjuk seorang perwakilan untuk melaporkan hasil
diskusinya di depan kelas secara bergantian.
Guru : “Anak-anak mohon perhatiannya, silakan
setiap kelompok menyiapkan satu orang untuk
membacakan hasil diskusi kelompok Anda di
depan kelas.”
Salah satu anak yang ditunjuk untuk mewakili
kelompoknya maju ke depan dan mempresentasikan hasil
diskusi kelompok mereka. Dari kegiatan ini guru mengetahui
seberapa jauh siswa mampu memahami materi yang telah
disampaikan.
3) Penutup dengan alokasi waktu 5 menit.
a) Guru dan siswa merefleksikan kembali hasil kegiatan
pembelajaran dengan materi nilai religius pada novel Sang
Pencerah.
127
Pada tahap ini guru menanyakan pada siswa apa yang
belum jelas dan belum dimengerti dari pelajaran yang telah
dibahas tadi. Tujuan kegiatan ini adalah agar guru dapat
mengetahui seberapa jauh siswa dapat memahami materi yang
telah diajarkan.
Guru : “Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apakah
ada yang belum Anda mengerti? Silahkan
Anda tanyakan bagian mana yang belum Anda
mengerti.”
b) Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan
salam.
Guru : “Jika tidak ada yang akan Anda tanyakan, kita
akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan
bacaan Hamdallah bersama-sama”
Guru dan siswa : “Alhamdulillahirabilalamin”
Guru : “Saya ucapkan terima kasih atas perhatian
Anda. Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.”
e. Sumber Belajar
Sumber belajar yang digunakan oleh siswa kelas XI SMA
untuk mempelajari struktur novel dan nilai religius novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral adalah guru, buku-buku
yang berkaitan dengan struktur dan nilai religius sastra, dan buku
paket Bahasa Indonesia kelas XI SMA.
128
f. Waktu
Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dapat diatur
sesuai dengan keleluasaan dan kedalaman materi. Dalam
pembelajaran novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
sebaiknya 4 jam pelajaran (2x pertemuan).
Misalnya untuk menyampaikan materi yang panjang dan
mendalam perlu waktu yang lebih lama. Dalam pembelajaran novel
sebaiknya satu minggu sebelum dimulai pembelajaran siswa
diminta untuk membaca terlebih dahulu di rumah.
g. Evaluasi pembelajaran sastra
Penilaian proses dan hasil sastra di SMA dapat berlangsung
lewat kegiatan, baik lisan maupun tertulis. Evaluasi yang
digunakan dalam pembelajaran novel Sang Pencerah secara
tertulis menggunakan tes esai.
Soal bentuk tes esai :
a. Jelaskan hubungan antara tema dengan alur dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
b. […] Yang merasa tertusuk lebih dulu dengan pertanyaankujustru bapakku sendiri. “Maksudmu dibuat sederhana itu apa,Wis?”[…]
“Maksudnya sederhana itu cukup berdoa saja, Pak. Tidakperlu dengan upacara berlebihan apalagi dengan memberikansesajen”. Aku memantapkan hatiku dalam memberikanjawaban sambil tetap berusaha menjaga kesantunan “uangpembuatan sesajen itu bisa dimanfaatkan sebagai sedekah bagifakir miskin sehingga hasilnya akan lebih jelas.”
Dan kini perdebatan di antara anggota keluargaku benar-benar terjadi setelah Mas Noor juga ikut angkat bicara. “Kalau
129
untuk soal sedekah itu tidak usah khawatir, Wis. Masjid Gedheselalu melakukan pemberian sedekah setiap hari Jumatsehingga umat Islam mendadak jadi banyak terlihat pada hariitu.” Nada suara Mas Noor tegas seperti biasa. “Kalau nyadranini isinya hanya membaca doa-doa saja, dan tidak ada orangyang mau datang berdoa, lantas siapa mau yang bertanggungjawab? Dan bagaimana kita menjelaskannya kepada NgarsaDalem?” (Sang Pencerah, 2010: 83-84).
Bagaimana pendapatmu, apakah penggalan kutipan disajikan
dengan nilai estetis?
c. Sebutkan hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya pada
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
d. Bagaimanakah nilai religius yang terdapat dalam novel, apakah
Anda merasa dibimbing setelah membaca novel tersebut?
130
BAB VPENUTUP
Hal-hal yang dipaparkan di dalam bab ini adalah simpulan dan saran.
Simpulan berisi jawaban padat hasil analisis data dari penelitian ini, sedangkan
saran berisi masukan penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada analisis dan pembahasan data hasil penelitian,
penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut.
1. Struktur pada novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
Struktur novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral yang
terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar dan amanat secara padu
membangun cerita yang mempunyai nilai estetis dan nilai religius.
2. Nilai religius novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
Nilai religius novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
mencakup dua aspek yaitu: (a) hubungan manusia dengan Tuhan meliputi
kewajiban salat, tawakal, jujur, syukur, pemimpin harus bertanggung
jawab, Islam adalah agama yang membawa rahmat, dan tidak boleh taklid
dalam beragama, (b) hubungan manusia dengan manusia meliputi
hubungan yang baik antara Darwis dengan bapak/ibu, menjalin
pertemanan, menghormati guru, menyantuni anak yatim, dan menikah, (c)
hubungan manusia dengan alam sekitar yaitu bahwa pohon bukan untuk
disembah. Nilai-nilai religius itu dikemas dalam bentuk cerita yang indah
dan tidak bersifat menggurui.
130
131
3. Skenario Pembelajaran Novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
di kelas XI SMA.
Tujuan dari pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
menggunakan kemampuan dasar dan indikator belajar sebagai ganti tujuan
pembelajaran umum dan khusus. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, pembelajaran sasta di
SMA meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.
Standar kompetensi dalam pembelajaran sastra adalah memahami berbagai
hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan, kompetensi dasar dalam
pembelajaran sastra disesuaikan dengan silabus adalah menganalisis
unsur-unsur novel Indonesia/terjemahan, sedangkan indikator pembelajar-
an sastra yaitu menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur,
tema, penokohan, dan latar).
Strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar adalah strategi
sastra yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu (1) tahap penjelajahan, (2)
tahap interpretasi, dan (3) tahap rekreasi. Dalam pemilihan bahan
pembelajaran juga harus memperhatikan sudut bahasa, latar belakang
budaya, dan psikologi. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi,
dan pemberian tugas. Sumber belajar yang dipakai adalah hasil karya
sastra atau novel, buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas XI
SMA, buku-buku tentang sastra, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Skenario pembelajaran nilai religious novel Sang Pencerah karya Akmal
Nasery Basral terdiri atas enam tahap yakni (a) pelacakan pendahuluan, (b)
132
penentuan sikap praktis, (c) introduksi, (d) penyajian, (e) diskusi, dan (f)
pengukuhan. Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran novel Sang
Pencerah secara tertulis dengan menggunakan tes esai.
B. Saran
1. Bagi peneliti berikutnya
Dalam penelitian ini, penulis hanya mengungkapkan sebagian kecil
dari novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Oleh karena itu,
bagi peneliti berikutnya perlu pengembangan lebih luas mengenai
permasalahan yang sama ataupun yang berbeda dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral.
2. Bagi pembaca agar lebih memahami makna dan pesan-pesan yang
disampaikan oleh pengarang dalam karya sastra khususnya novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral.
3. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi
pendidikan dan untuk menambah wawasan siswa dan kecintaan akan dunia
sastra diharapkan guru mampu menumbuhkembangkan minat siswanya
dalam dunia kesusastraan.
4. Bagi siswa, diharapkan dapat memperdalam keterampilan siswa dalam
berbahasa dan dapat menambah wawasan sastra bagi siswa.
DAFTAR PUSTAKA
Alwi, Hasan dkk. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.Jakarta: Balai Pustaka.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rineka Cipta.
Atmosuwito, Subijantoro. 1989. Perihal Sastra dan Religiusitas dalam Sastra.Bandung: Sinar Baru.
Baribin, Raminah. 1985. Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Semarang: IKIPSemarang Press.
Basral, Akmal Nasery. 2010. Sang Pencerah. Jakarta: Mizan Pustaka.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia EdisiKeempat. Jakarta: Balai Pustaka.
Hamalik, Oemar. 2010. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
Hamalik, Oemar. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
Ihsan, Fuad.2011. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Mangunwijaya, Y. B. 1982. Satra dan Religiositas. Jakarta: Sinar Harapan.
Milllati, Uswah. 2012. .”Nilai-Nilai Religius dalam Novel Ketika Cinta BertasbihI karya Habiburrahman El-Shirazy dan Relevansi Pembelajarannya diSMA”. Skripsi. Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Mulyasa, E. 2011. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: RemajaRosdakarya.
Muslich, Mansnur. 2009. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi danKontekstual. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Nur Ghufron, M. dan Rini Risnawati S. Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa BerbasisKompetensi. Yogyakarta: BPFE.
Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Pedoman Umum EjaanBahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: Balai Pustaka.
Rahmanto, B. 1988. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: Kanisius.
Rusyana, Yus. 1982. Metode Pengajaran Sastra. Bandung: PT Mangle Panglipur.
Rusyana, Yus.1984. Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan. Bandung:CV Diponegoro.
SISDIKNAS. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
SM, Ismail. 2009. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM.Semarang: Rasail Media Group.
Stanton, Robert. 2007. Teori Fiksi (Terjemahan Sugihastuti dan Rossi Abi AlIrsyad). London: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Buku Asliditerbitkan tahun 1965).
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: DutaWacana University Press.
Sujiman, Panuti. 1988. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta: Pustaka Jaya.
Suyud. 2007. “Religiositas dalam Novel Lingkar Tanah Lingkar Air karya AhmadTohari”. Skripsi. Purworejo: Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Syukur, Ibrahim, Abdul. 2009. Metode Analisis Teks dan Wacana. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Tim Edukatif. 2007. Kompeten Bahasa dan Ssatra Indonesia untuk SMA KelasXI. Jakarta: Erlangga.
Yuni Purwanti, Marina. 2010. “Nilai Religiositas dalam Novel Tasawuf Cintakarya M.Hilmi As’ad”. Skripsi. Purworejo: Universitas MuhammadiyahPurworejo.
SINOPSIS NOVEL SANG PENCERAH
Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dengan
nama kecil Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai
Muhammad Sulaiman, khatib masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, dan seorang ibu
bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim yang juga seorang penghulu
Kasultanan yang cukup terpandang. Suatu ketika saat Darwis (KH Ahmad
Dahlan) diajak oleh ayahnya untuk menghadiri yasinan 40 hari meninggalnya
Bapak Pono dan tanpa sengaja mendengar pembicaraan ibu Pono dengan seorang
ibu tentang pelunasan hutang, sejak saat itulah Darwis berpikir apakah yasinan itu
merupakan suatu keharusan. Selain itu tentang tradisi padusan dan ruwatan yang
menurut Darwis tidak ada dalam syariat Islam. Sejak saat itulah pemikirannya
selalu muncul dan bahkan mulai menentang orang-orang di sekelilingnya.
Darwis berangkat menunaikan ibadah haji saat dia berumur 15 tahun.
Beliau mempelajari ilmu hadis, ilmu qira’at, ilmu hisab, ilmu nahwu, ilmu falaq
dari para syaikh di Mekah. Setelah lima tahun beliau menimba ilmu di Mekah
beliau kembali lagi ke Jawa dengan nama baru yakni Ahmad Dahlan, dan semua
orang menyetujui nama tersebut. Tak lama kemudian beliau menikah dengan Siti
Walidah anak dari Kiai Fadhil yang masih sepupunya. Dari pernikahannya itu
Kiai Dahlan dikaruniai dua orang putra dan empat orang putri. Kiai Ahmad
Dahlan diangkat sebagai khatib di masjid Gedhe untuk menggantikan posisi
Bapaknya (Kiai Haji Abu Bakar) yang wafat. Kiprahnya berdakwah dimulai dari
mendirikan Langgar yang digunakan beliau untuk memberikan pengajian kepada
Lampiran 1
para santrinya. Akhirnya untuk pertama kali Kiai Dahlan bertindak sebagai Khatib
Amin dalam shalat jum’at, dimana isi khutbah beliau sedikit membuat wajah Kiai
Penghulu tampak tertekan. Sejak saat itu Kiai Dahlan mendapat teguran dari Kiai
Penghulu, apalagi tentang pemikiran-pemikiran dan dan pendapat Kiai Dahlan
mengenai arah kiblat Masjid Gedhe yang salah hingga pada akhirnya
menimbulkan geger di Masjid Gedhe karena ada garis shaf baru. hal itu semakin
membuat Kiai Penghulu terbakar amarah dan menuduh Kiai Dahlan dan para
santrinya yang melakukan hal itu. Namun semua tuduhan itu tidak terbukti karena
yang melakukannya adalah Dirjo keponakan Kiai Penghulu.
Kiai Dahlan mendapat teguran dari Kiai Penghulu untuk menutup Langgar
Kidul, namun Kiai Dahlan tetap tidak akan menutup Langgar Kidul. Hingga pada
suatu suatu malam terjadi peristiwa yang begitu menyakitkan bagi Kiai Dahlan
dan para santri-santrinya yaitu dihancurkannya Langgar Kidul oleh orang-orang
suruhan Kiai Penghulu. Setelah kejadian itu Kiai Dahlan berniat meningalkan
Kauman dan pergi ke Semarang, namun niat itu dicegah oleh Kiai Saleh hingga
Kiai Dahlan mau kembali ke Kauman dan membangun kembali Langgar Kidul
yang telah runtuh. Kiai Dahlan kemudian mengundurkan diri sebagai Khatib
Amin di Masjid Gedhe.
Sri Sultan Hamungkubuwono kemudian mengirim Kiai Dahlan untuk
melaksanakan ibadah haji yang kedua untuk memperdalam ilmu agama yang akan
dibiyayai sepenuhnya oleh Keraton. Disana beliau bertemu dengan Syaikh Rasyid
Ridha, seorang pembaharu pemikiran Islam yang juga murid dari Syaikh
Jamaluddin Al Afghani dan Syaikh Mualana Abduh. Sepulang menunaikan
ibadah haji Kiai Dahlan bergabung dengan Budi Utomo dan mengajar sekolah
Belanda yang bernama Kweek School. Kiai Dahlan dituduh sebagai Kiai Kafir
karena memakai pakaian mirip orang Belanda yakni memakai jas dan sepatu, juga
karena Kiai Dahlan sering memainkan alat musik biola. Selain itu juga karena
Kiai Dahlan membuka sekolah dengan menggunakan peralatan seperti meja dan
kursi yang dianggap orang-orang itu merupakan perlengkapan orang kafir.
Niatnya untuk mendirikan Muhammadiyah terus diperjuangkan oleh Kiai Dahlan
walaupun berbagai cobaan dan tuduhan tetap tidak membuat Kiai Dahlan surut.
Dengan diterima istri tercinta Siti Walidah dan lima murid-murid setianya yaitu
Sudja, Sangidu, Fakhrudin, Hisyam dan Dirjo akhirnya Persyarikatan
Muhammadiyah disetujui oleh Kiai Penghulu yang pada awalnya tidak
menyetujui adanya Muhammadiyah dan hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai
Penghulu serta Kiai di Kauman membaik.
Biografi Pengarang Sang Pencerah
Pengarang novel Sang Pencerah adalah seorang laki-laki yang bernama
Akmal nasery Basral. Pria kelahiran Jakarta, 28 April 1968 adalah seorang
wartawan dan sastrawan Indonesia. Kumpulan cerpen pertamanya Ada Seseorang
di Kepalaku Yang Bukan Aku (2006) yang terdiri dari 13 cerpen. Sebagai
wartawan dia pernah bekerja untuk majalah mingguan Gatra (1994-1998),
Gamma (1999), majalah Tempo (2004-sekarang). Dia dapat memaparkan suatu
nilai yang kreatif dan berbobot dengan menggunakan bahasa sederhana yang
terkadang masih lekat dengan Jawa.
Merintis karir di dunia jurnalistik sejak 1994, dia pernah bekerja sebagai
wartawan di tiga majalah berita mingguan (Gatra, Gamma, Tempo). Di bidang
kesusastraan, Akmal yang menyukai gaya bercerita Jonathan Safran Foer dan
Haruki Murakami ini sedang menyelesaikan naskah novelnya, Las Palabras de
amor, yang merupakan alegori Indonesia periode 1980-an sampai 2000an.
Di bidang perfilman, saat ini Akmal merupakan penyedia cerita program
FTV 20 wajah Indonesia, program khusus kanal SCTV yang dikerjakan rumah
produksi Citra Sinema pimpinan Deddy Mizwar. Di tengah-tengah kesibukan
mengerjakan FTV itu, Akmal yang juga penikmat seri documenter Don’t Tell My
Mother yang dipandu Diego ini sedang menggodok film documenter yang akan
disutradarainya sendiri, dibantu oleh yayasan Mizan/ Mizan Productions.
Di antara du kutub dunia sastra dan film itu yang ditekuninya, ayah tiga
putri ini masih bersentuhan dengan dunia music cukup intens lewat
keterlibatannya dalam memoles sebuah band pop secara rutin. Jika tidak ada aral
melintang, sebuah bukunya tentang profil dan perjalanan dua orchestra terkemuka
di tanah air juga akan terbit.
Lampiran 2
1. Tabel Struktur Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral
No Unsur pembentuk karya sastra Penyajian Data
1 Tema 83, 84, 110, 111, 241, 245, 360,368, 294, 399, 426, 442, 443.
2 Tokoh dan penokohan 294, 6, 82, 45, 67, 74, 78, 79, 150,93, 238, 128, 182, 129, 140, 178,222, 263, 303, 312, 314, 413.
3 Alura. Awal
1. Paparan 62. Rangsangan 71
3. Gawatan 206b. Tengah
1. Tikaian 842. Rumitan 204, 206, 2113. Klimaks 244, 245
c. Akhir1. Leraian 260, 2622. Selesaian 417, 424.
4. Latar
a. Latar tempat 141, 143, 267, 239, 402, 403,
b. Latar waktu 125, 254, 100, 96, 21, 101, 160,137, 254, 164, 450, 11, 160, 161.
c. Latar sosial 174, 175, 46, 93, 190, 129, 441,93.
5. Sudut pandang 90, 260.
6. Amanat 90, 229, 391, 81, 263.
Lampiran 3
2. Tabel Nilai Religius yang Ada dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal
Nasery Basral
No Nilai-Nilai Religius Penyajian Data
1. Hubungan Manusia dengan
Tuhan
212,161, 91, 46, 7-8, 175
2. Hubungan Manusia dengan
Manusia
11, 14, 24, 49, 63, 65, 156.
3. Hubungan Manusia dengan
Alam
90
Lampiran 4SILABUS
Nama Sekolah :SMA Negeri 1 KlirongMata Pelajaran : Bahasa IndonesiaKelas : XISemester : 1Standar Kompetensi : Membaca
7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia / Novel Terjemahan
KompetensiDasar
MateriPembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Indikator PenilaianAlokasiWaktu
Sumber /Bahan
7.2 Menganalisisunsur-unsurinstrinsik danekstrinsiknovelIndonesia.
Novel Indonesiadan novelterjemahan.- Unsur-unsur
intrinsik(alur,tema,penokohan,sudut pandang,latar, danamanat).
- Unsur ekstrinsik(nilai religius)
- Membaca novel Indonesiadan
- Menganalisis unsur-unsurekstrinsik dan intrinsik(alur, tema, penokohan,sudut pandang, latar, danamanat) novel Indonesiadan novel Terjemahan.
- Membandingkan unsurekstrinsik dan intrinsiknovel Indonesiadengannovel terjemahan.
- Menganalisis unsur-unsurekstrinsik (niali religius)dan intrinsik novelIndonesia (tema, tokohdan penokohan, alur,latar, dan amanat)
- Menganalisis unsur-unsurekstrinsik dan intrinsiknovel terjemahan.
- Membandingkan unsurekstrinsik dan intrinsiknovel Indonesia dan novelterjemahan.
Jenis tagihan- Tugas individu- Tugas kelompok-UlanganBentuk instrumen- Uraian bebas- Pilihan ganda- Jawaban singkatJenis tagihan- Tugas kelompok- Tugas kelompok- UlanganBentuk instrumen- Uraian bebas- Pilihan ganda- Jawaban singkat
4 Novel SangPencerahkaryaAkmalNaseryBasral
Purworejo, September 2012Guru Mata Pelajaran
Eni Kusrini
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Tingkat Sekolah : SMA Negeri 1 Klirong
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas/Semester : XI/I
Standar Kompetensi : Memahami cerita pendek, novel dan hikayat
Kompetensi Dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel
Indonesia/ terjemahan
Indikator :
a) Siswa mampu menceritakan isi novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral
b) Siswa dapat menjelaskan struktur dalam novel Sang
Pencerah
c) Siswa dapat menjelaskan nilai religius dalam novel
Sang Pencerah
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
A. Tujuan Pembelajaran
1) Siswa mampu menceritakan isi novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery
Basral
2) Siswa dapat menjelaskan struktur dalam novel Sang Pencerah
3) Siswa dapat menjelaskan nilai religius dalam novel Sang Pencerah
Lampiran 5
B. Materi Pembelajaran
Novel adalah novel adalah suatu karangan prosa yang panjang yang
mengandung rangkaian cerita yang melukiskan kehidupan para tokoh secara
imajinatif berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional dalam
masyarakat.
Struktur novel
1. Struktur novel
Analisis struktural merupakan prioritas pertama sebelum
diterapkannya analisis yang lain. Unsur-unsur struktur karya sastra
meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat dan pusat
pengisahan
a. Tema
Di bawah ini beberapa pendapat mengenai tema yang
dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut:
1) Nurgiyantoro (2011:68) mengatakan, tema merupakan keseluruhan
yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” di
dalam cerita yang mendukungnya.
2) Sudjiman (1986: 50) mengatakan, tema adalah gagasan, ide atau
pikiran utama yang mendasari karya sastra.
Menurut Nurgiyantoro, tema dibedakan menjadi dua bagian
yaitu tema utama yang disebut tema mayor yang artinya makna pokok
yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum karya itu. Tema mayor
ditentukan dengan cara menentukan persoalan yang paling menonjol,
yang paling banyak konflik dan waktu penceritaannya, sedangkan tema
tambahan disebut tema minor. Tema minor merupakan tema yang
kedua yaitu makna yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu
cerita dan diidentifikasikan sebagai makna bagian atau makna
tambahan.
Tema adalah ide cerita yang merupakan dasar untuk
pengembangan cerita yang menjiwai seluruh bagian cerita. Kedudukan
tema dalam novel sangat penting, karena tanpa tema sebuah karya
tidak memiliki makna.
b. Tokoh dan Penokohan
Setiap tokoh dalam suatu cerita mempunyai ciri-ciri tersendiri
atau watak yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Sudjiman
(1988: 16), tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa
atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita.
Tokoh adalah pelaku rekaan yang mengalami peristiwa atau
berkelakuan pada berbagai peristiwa (Nurgiyantoro, 2010: 164),
sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang
seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2010:
165).
Nurgiyantoro (2010: 176-191), membedakan tokoh :
a) Tokoh utama dan tokoh tambahan
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya
dalam novel yang bersangkutan. Penggambaran tokoh utama
banyak berhubungan dengan tokoh lain dan sering muncul dalam
cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit dimunculkan
dalam cerita, kehadirannya jika ada keterkaitannya dengan tokoh
utama.
b) Tokoh protagonis dan antagonis
Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang
salah satu jenisnya secara popular disebut tokoh hero yang
merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal
bagi kita. Tokoh protagonis biasanya menarik simpati pembaca.
Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu menyebabkan konflik
bagi tokoh protagonis.
c) Tokoh sederhana dan tokoh bulat
Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu
kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Tokoh
bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai
kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya.
d) Tokoh statis dan tokoh berkembang
Tokoh statis adalah tokoh yang memiliki sikap dan watak
yang relatif tetap, tak berkembang, sejak awal sampai akhir cerita.
Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan
dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan
perubahan) peristiwa dan plot yang dikisahkan.
e) Tokoh tipikal dan tokoh netral
Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan
keadaan individualitasnya. Tokoh netral adalah tokoh cerita yang
bereksistensi demi cerita itu sendiri.
Menurut Sudjiman (1988: 24-26), cara penggambaran
penokohan, menggunakan metode analitik dan metode dramatik.
Metode analitik adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan memberi
deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Metode
dramatik adalah pelukisan tokoh cerita dilakukan secara tidak
langsung, pengarang membiarkan pembaca untuk menunjukkan
kehadirannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan,
baik secara verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan
atau tingkah laku, dan juga melalui peristiwa yang terjadi.
c. Alur
Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2010: 113), alur adalah cerita yang
berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan
secara sebab akibat, peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan
terjadinya peristiwa lain.
Menurut Sudjiman (1988: 30-36), struktur alur dapat dibagi
menjadi tiga bagian sebagai berikut.
a) Awal
(1) Paparan (exposition), berisi peristiwa awal yang memberikan
gambaran masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita.
(2) Rangsangan (inciting moment), merupakan bagian alur yang
mengarah pada terjadinya tindakan awal sang tokoh.
(3) Gawatan (rising action), merupakan bagian dari alur yang
menunjukkan gerak menanjak masalah.
b) Tengah
(1) Tikaian (confict), menggambarkan perbedaan sikap, keinginan,
dan pandangan masalah para tokoh.
(2) Rumitan (complication), menunjukkan tikaian yang semakin
tajam dan rumit.
(3) Klimaks (climax), menunjukkan ketajaman konflik yang
dihadapi para tokoh.
c) Akhir
(1) Leraian (falling action), menggambarkan mulai cairnya
kebekuan dan kekakuan sikap para tokoh yang terjadi hingga
klimaks.
(2) Selesaian (denaument), memberikan gambaran nasib para
tokoh terhadap penyelesaian.
d. Latar
Latar merupakan peristiwa-peristiwa dalam cerita terjadi pada
suatu waktu atau dalam suatu rentang waktu tertentu dan pada suatu
tempat tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa segala
keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang,
dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra membangun
latar cerita (Sudjiman, 1988: 46).
Menurut Sudjiman (1991:480), latar adalah segala keterangan
waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra.
1) Latar Tempat
Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa
yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi.
2) Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan”
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya
fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya dihubungkan dengan
waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan
dengan peristiwa sejarah.
3) Latar Sosial
Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan
dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang
diceritakan dalam karya fiksi.
e. Amanat
Dari sebuah karya sastra dapat diangkat suatu ajaran moral,
atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam
cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan
dengan ajaran moral tertentu. Amanat pada sebuah karya sastra
ditampilkan secara implisit (tak langsung) ataupun eksplisit (langsung)
(Sudjiman, 1988: 57).
2. Unsur Ekstrinsik
Unsur ekstrinsik adalah unsur yang secara tidak langsung melekat
dan membangun suatu karya sastra, terlepas dari yang diceritakan. Unsur
intrinsik meliputi:
a. Latar belaknag kehidupan pengarang dan kondisi zaman saat karya
sastra diciptakan
b. Status sosial
c. Budaya
d. Agama
e. Politik dan lain-lain
Unsur ekstrinsik yang menjadi materi dalam novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral, yakni berkaitan dengan nilai religius
mengenai ajaran Islam di dalam kehidupan.
C. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam novel Sang Pencerah
karya Akmal Nasery Basral antara lain:
a. ceramah
b. diskusi
c. pemberian tugas
D. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Tahap awal
a) Guru memberikan salam dan melakukan absensi pada siswa;
b) Guru menjelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran;
c) Memotivasi siswa dengan mengarahkan pada situasi pembelajaran.
2. Kegiatan inti
a) Guru menjelaskan mengenai struktur (tema, tokoh dan penokohan,
alur, latar, sudut pandang dan amanat) dan ekstrinsik (nilai religius
yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan
manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya)
b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai
materi yang belum jelas dan belum dimengerti.
c) Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok
d) Siswa diminta membaca novel Sang Pencerah secara bergantian
e) Siswa mendiskusikan novel Sang Pencerah serta mencari struktur
(tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang dan amanat)
dan ekstrinsik (nilai religius yang meliputi hubungan manusia dengan
Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam
sekitarnya)
3. Penutup
a) Guru menyuruh siswa melanjutkan tugasnya masing-masing di rumah.
b) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam
dan berdoa.
Pertemuan 2
1. Tahap awal
a) Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam
dan melakukan absensi.
b) Guru mengulas materi yang telah dijelaskan pada pertemuan
sebelumnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa.
2. Kegiatan inti
a) Guru dan siswa mendiskusikan tentang kesulitan yang ditemukan saat
mengerjakan tugas tentang struktur (tema, tokoh dan penokohan, alur,
latar, sudut pandang dan amanat) dan ekstrinsik (nilai religius yang
meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan alam sekitarnya).
b) Guru meminta siswa perwakilan untuk maju dari masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan jawaban yang ada.
c) Siswa bersama guru berdiskusi membahas struktur (tema, tokoh dan
penokohan, alur, latar, sudut pandang dan amanat) dan ekstrinsik (nilai
religius yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya).
3. Penutup
a) Refleksi.
b) Menyimpulkan materi pembelajaran.
c) Evaluasi.
E. Sumber Belajar
1. Buku wajib Kompeten Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA Kelas XI
2. LKS bahasa Indonesia
3. Buku Teori Pengkajian Fiksi karya Nurgiyantoro
4. Buku Metode Pengajaran Sastra karya Rusyana
F. Evaluasi
1. Evaluasi proses
Bacalah novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral
2. Evaluasi hasil
a) Jelaskan hubungan antara tema dengan alur dalam novel Sang
Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
b) […] Yang merasa tertusuk lebih dulu dengan pertanyaanku justrubapakku sendiri. “Maksudmu dibuat sederhana itu apa, Wis?”[…]“Maksudnya sederhana itu cukup berdoa saja, Pak. Tidak perlu denganupacara berlebihan apalagi dengan memberikan sesajen”. Akumemantapkan hatiku dalam memberikan jawaban sambil tetapberusaha menjaga kesantunan “uang pembuatan sesajen itu bisadimanfaatkan sebagai sedekah bagi fakir miskin sehingga hasilnyaakan lebih jelas.”
Dan kini perdebatan di antara anggota keluargaku benar-benarterjadi setelah Mas Noor juga ikut angkat bicara. “Kalau untuk soalsedekah itu tidak usah khawatir, Wis. Masjid Gedhe selalu melakukanpemberian sedekah setiap hari Jumat sehingga umat Islam mendadakjadi banyak terlihat pada hari itu.” Nada suara Mas Noor tegas sepertibiasa. “Kalau nyadran ini isinya hanya membaca doa-doa saja, dantidak ada orang yang mau datang berdoa, lantas siapa mau yangbertanggung jawab? Dan bagaimana kita menjelaskannya kepadaNgarsa Dalem?” (Sang Pencerah, 2010: 83-84).
Bagaimana pendapatmu, apakah penggalan kutipan disajikan dengan
nilai estetis?
c) Jelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya pada novel
Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral?
d) Bagaimanakah nilai religius yang terdapat dalam novel, apakah Anda
merasa dibimbing setelah membaca novel tersebut?
Skor Penilaian
Skor penilaian no. 1 = 25
Skor penilaian no. 2 = 25
Skor penilaian no. 3 = 25
Skor penilaian no. 4 = 25
Nilai total = 100
Kebumen, September 2012Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Nur Chafid, S.Pd. Eni Kusrini
Kunci Jawaban Evaluasi
1. Hubungan antara Tema dengan Alur
Tema novel Sang Pencerah adalah perjuangan memurnikan ajaran
Islam dari unsur bidah dan perjuangan mendirikan Muhammadiyah sebagai
wadah organisasinya. Untuk membawa tema ini, pengarang membuat cerita
mengenai seseorang yang mempunyai sifat pemaaf, dan tidak pendendam.
Dari hal tesebut muncul masalah-masalah yang membuat cerita terus bergerak
dalam novel Sang Pencerah.
Konflik dalam novel Sang Pencerah berawal dari usulan Kiai Dahlan
mengenai upacara nyadran, pendapatnya yang saat itu membuat perdebatan
di antara anggota keluarganya yang mengakibatkan konflik berlanjut yakni
saat Kiai Dahlan mengungkapkan bahwa arah kiblat Masjid Gedhe salah.
Selain itu beliau berpakaian dan mendirikan sekolah yang dituding sebagai
Kyai Kafir karena mirip dengan orang kafir.
2. […] Yang merasa tertusuk lebih dulu dengan pertanyaanku justru bapakkusendiri. “Maksudmu dibuat sederhana itu apa, Wis?”[…]
“Maksudnya sederhana itu cukup berdoa saja, Pak. Tidak perludengan upacara berlebihan apalagi dengan memberikan sesajen”. Akumemantapkan hatiku dalam memberikan jawaban sambil tetap berusahamenjaga kesantunan “uang pembuatan sesajen itu bisa dimanfaatkansebagai sedekah bagi fakir miskin sehingga hasilnya akan lebih jelas.”
Dan kini perdebatan di antara anggota keluargaku benar-benarterjadi setelah Mas Noor juga ikut angkat bicara. “Kalau untuk soalsedekah itu tidak usah khawatir, Wis. Masjid Gedhe selalu melakukanpemberian sedekah setiap hari Jumat sehingga umat Islam mendadak jadibanyak terlihat pada hari itu.” Nada suara Mas Noor tegas seperti biasa.“Kalau nyadran ini isinya hanya membaca doa-doa saja, dan tidak adaorang yang mau datang berdoa, lantas siapa mau yang bertanggung jawab?
Dan bagaimana kita menjelaskannya kepada Ngarsa Dalem?” (SangPencerah, 2010: 83-84).
Dalam penggalan kutipan di atas, digambarkan Darwis ditanya orangtuanya maksud dari ucapannya mengenai upacara nyadran yang dibuatsederhana saja. Kemudian jawaban yang diberikan oleh Darwis tidakmenyinggung perasaan orang tuanya dan orang-orang yang menghadirirapat takmir tersebut. Jawaban yang disampaikan Darwis dengankesantunan. Hal itu terlihat harmonis jika dikaitkan dengan tema noveladalah memurnikan ajaran Islam dari unsur bidah dan perjuanganmendirikan Muhammadiyah. Jika Darwis menjawab pertanyaan denganemosional maka dia bukan seorang pencerah seperti tema yang terdapatdalam novel.
3. Hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya pada novel Sang Pencerahkarya Akmal Nasery Basral?
1) Setiap Muslim Wajib Melaksanakan Salat Lima Waktu Sehari
2) Tawakkal kepada Allah
3) Sifat Syukur kepada Allah
4) Sifat Jujur ketika Berdagang
5) Pemimpin yang Bertanggung Jawab
6) Islam adalah Agama yang Membawa Rahmat
7) Tidak Boleh Taklid dalam Beragama
4. Setelah membaca novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral saya
mendapatkan pelajaran bahwa dalam hidup kita tidak boleh menyekutukan
Allah dengan makhluk-Nya, tidak boleh menuduh kafir terhadap sesama
muslim, dalam menyampaikan dakwah perlu mengetahui sasarannya, dan
saling membantu ketika saudara kesusahan,