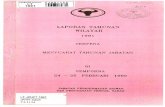Menanti Wangi Bunga dan Manisnya Buah Pemekaran Wilayah
Transcript of Menanti Wangi Bunga dan Manisnya Buah Pemekaran Wilayah
1
MENANTI WANGI BUNGA DAN MANISNYA BUAH PEMEKARAN WILAYAH :
Sebuah Catatan Pengamatan Atas Perjalanan Desentralisasi di Sumatera Utara 1
Zulkifli B. Lubis2
Pengantar
Pertama-tama, mari kita coba analogikan konsep pemekaran wilayah dalam kerangka
desentralisasi dengan mekarnya sekuntum bunga. Sebatang tumbuhan, lazimnya, akan
tiba pada suatu saat dimana ia berbunga, menebarkan pesona keindahan dan aroma
wangi. Ketika itu kumbang, lebah, dan serangga lain datang menikmati sari bunga, lalu
pergi. Meskipun mereka mereguk nikmatnya sari dan kemudian membiarkan bunga
layu, tapi berikutnya, penyerbukan tanpa sengaja yang mereka jejakkan membuat putik
terus berkembang menjadi buah, yang ketika masak kelak akan terasa manis.
Euforia reformasi sejak 1998 dan, tentu saja, tuntutan perubahan zaman yang
tidak bisa dielakkan, membuat harapan sebagian masyarakat Indonesia menjadi mekar,
terlebih setelah disahkannya UU No. 22 Thn 1999 dan revisinya UU No. 32 Tahun 2004.
Dengan kebijakan otonomi daerah dimungkinkan terjadinya pembelahan-pembelahan
wilayah administratif yang kemudian kita kenal luas dengan sebutan pemekaran wilayah,
suatu proses politik yang diwadahi melalui Pasal 4-5 UU No. 22 /99 dan juga UU No.
32/2004. Maraknya usaha pemekaran wilayah di seluruh Indonesia, sejak 1999 hingga
sekarang, adalah bentuk keterpesonaan sebagian besar masyarakat di daerah-daerah
yang ditebarkan oleh „bunga‟ kebijakan otonomi. Ibarat kumbang, lebah, semut dan
aneka serangga lain yang segera mengendus wangi serta mengerubungi dan
memperebutkan sang bunga, kita juga lalu melihat hiruk pikuknya gerak manusia
Indonesia (atas nama kepentingan daerah, suku, golongan, agama, ekonomi, politik, dan
lain sebagainya secara laten maupun manifes) berlomba mengajukan usulan untuk
pemekaran wilayah. Hasil sementara adalah telah terwujudnya 33 propinsi dan 300-an
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
„Bunga‟ kebijakan otonomi telah dan terus mekar, dan pemekaran wilayah masih
tetap menebar pesona keindahan serta aroma wangi. Tetapi apakah bunga-bunga yang
telah mekar itu telah bersalin rupa menjadi putik yang segar untuk segera menjadi buah
1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Sumatera dalam Perspektif Sejarah;
diselenggarakan di Medan pada tanggal 24-27 April 2007, oleh Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat
Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2 Saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Departemen Antropologi Fisip USU.
2
manis yang memberi kelezatan ? Buah manis yang (Insya Allah) memberi kelezatan itu,
dalam terminologi kebijakan otonomi daerah, diistilahkan dengan kesejahteraan
masyarakat3. Pertanyaannya, apakah pemekaran wilayah yang sudah berlangsung telah
bergerak di jalur yang benar menuju kesejahteraan masyarakat ? Sebuah pertanyaan
yang akhir-akhir ini semakin gencar dikumandangkan oleh banyak pihak –terlepas hal
itu dipertanyakan secara tulus ikhlas karena kerisauan akan kenyataan yang terjadi di
lapangan atau dilandasi adanya kepentingan politik tertentu yang diarahkan kepada
stigmatisasi pemekaran wilayah.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan di atas, karena dalam
pandangan penulis, masa yang singkat sejak berlakunya pemekaran wilayah belum pada
saatnya untuk berharap dapat memetik buah yang manis. Pendek kata, kita semua masih
dalam masa penantian, yaitu menanti proses metamorfosis dari wangi bunga ke buah
manis pemekaran wilayah. Yang perlu kita periksa seksama (analisis) dan pastikan
(intervensi kebijakan) adalah bahwa proses perubahan itu berlangsung secara sehat dan
terjaga. Dan yang tidak semestinya kita lakukan adalah memotong sendiri atau
membiarkan pihak tertentu memotong atau merampas bunga itu, sehingga tak mungkin
kita menanti datangnya buah. Beranjak dari pengamatan dan pemeriksaaan terhadap
perjalanan otonomi daerah di Sumatera Utara khususnya, tulisan ini mencoba mengurai
beberapa aspek yang tampaknya potensial menginterupsi proses perubahan yang sehat
menuju buah manis pemekaran wilayah. Meskipun kerisauan, kekhawatiran dan rasa
pesimisme mulai menyergap batin kita menyaksikan perjalanan otonomi (seperti kita
melihat sekuntum bunga layu), penulis percaya bahwa di balik kelopaknya yang
mengerut telah tumbuh putik yang, jika kita tetap rawat dan jaga dengan baik, kelak
akan menghasilkan buah.
Sekilas tentang kebijakan desentralisasi
Salah satu dari banyak aspek desentralisasi yang diatur dalam UU No. 22 Thn 1999 dan
UU No. 32 Thn 2004, pasal-pasal mengenai pembentukan daerah di dalam undang-
undang tersebut tampaknya mengundang gairah yang demikian besar bagi masyarakat
Indonesia. Rasa terkekang dalam kerangka susunan wilayah administratif pemerintahan
zaman Orde Baru yang terkesan dibakukan dan diimbuhi dengan kekangan ruang gerak
partisipasi politik rakyat, membuat peluang „mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat‟4
yang diberikan oleh undang-undang Otda langsung dimanfaatkan oleh daerah-daerah.
3 Tujuan dari pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) sebagaimana dituliskan dalam
dokumen RPJMN 2004-2009 adalah kesejahteraan masyarakat. Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah,
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. 4 Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999.
3
Urusan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat tersebut seyogiyanya
dapat dilakukan melalui proses pembentukan daerah baru (baik melalui penggabungan
beberapa daerah maupun pemekaran daerah) dan pembentukan kawasan khusus,
tampak bahwa pilihan paling populer sejauh ini adalah pemekaran daerah. Sejak 1999
wilayah propinsi telah mekar menjadi 33 setelah dibentuknya propinsi Maluku Utara
(1999), Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo (2000), Irian Jaya Barat (2001),
Kepulauan Riau (2002), Sulawesi Barat (2004). Di Sumatera Utara, wacana yang sudah
lama berkembang dan mengundang reaksi pro-kontra di tengah masyarakat adalah
pembentukan Propinsi Tapanuli.
Menurut Undang-undang5 proses pemekaran wilayah atau pembentukan daerah
otonom baru harus memenuhi syarat (1) administratif, (2) teknis dan (3) fisik
kewilayahan. Syarat administratif meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota
dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD
provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri (untuk kasus
pemekaran propinsi), dan meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta
rekomendasi Menteri Dalam Negeri (untuk kasus pemekaran kabupaten/kota).
Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang
mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan syarat fisik meliputi
paling sedikit 5 kabupaten kota untuk pembentukan provinsi, 7 kecamatan untuk
pembentukan kabupaten, 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota,
sarana dan prasarana pemerintahan.
Tahap selanjutnya setelah terbentuknya daerah otonom baru adalah penunjukan
penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian,
pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah. Dalam waktu kurang lebih
satu tahun kemudian diselenggarakan pemilihan kepala daerah, yang sejak 2005 telah
diatur melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung). Dengan demikian
ada dua tahapan krusial yang harus didahului sebelum suatu daerah otonom baru benar-
benar bisa berdiri, yaitu (1) tahapan pengajuan usulan pemekaran wilayah sesuai dengan
jenjang administratif di atas sampai dengan mendapat persetujuan DPR yang ditandai
dengan pengesahan UU; (2) tahapan pembenahan birokrasi dan pemilihan kepala
daerah definitif melalui Pilkada.
Cukup menarik untuk mengamati bahwa kedua tahapan itu biasanya berlangsung
dan terbangun dalam dua simpul wacana serta argumentasi yang berbeda. Pada tahapan
5 Undang-Undang No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4
pertama, yaitu proses penggalangan dukungan dan pengajuan usulan pemekaran, isu-isu
utama atau wacana yang sering ditonjolkan oleh elit-elit yang menggerakkan pemekaran
antara lain adalah ketertinggalan daerah yang akan dimekarkan dari sentuhan program
pembangunan (kurang mendapat perhatian dari pemerintah di propinsi/kabupaten
induk), jarak dan letak geografis yang cukup jauh dari ibukota sehingga rentang kendali
pemerintahan menjadi panjang dan makan waktu, serta dukungan kemampuan ekonomi
dan potensi daerah. Itu adalah wacana yang diungkapkan secara objektif ke permukaan
dan biasanya diimbuhi dengan dokumen hasil kajian potensi sesuai dengan persyaratan
formal (sesuai rumus perhitungan) pemekaran wilayah. Wacana lain yang tidak cukup
terang diungkapkan (disamarkan sedemikian rupa) adalah isu-isu sosial budaya seperti
marjinalisasi golongan penduduk tertentu, rivalitas dan friksi satuan-satuan sosial yang
bersifat laten (berbasis etnik, agama, kelompok klen, sentimen kedaerahan), serta
adanya kepentingan elit politik dan elit ekonomi.
Sementara itu, pada tahapan kedua, yaitu proses pembenahan birokrasi dan
pemilihan kepala daerah definitif, wacana yang lebih menonjol terlihat antara lain adalah
isu putra daerah, transaksi politik untuk memenangkan Pilkada, kolaborasi elit politik
lokal dan elit ekonomi, kepentingan untuk mengakomodasi „TS‟ (tim sukses) dalam
jabatan birokrasi dan pengelolaan dana pembangunan, polarisasi dan marginalisasi PNS
di dalam satuan birokrasi pemerintah daerah, dan isu-isu terjadinya fragmentasi sosial di
tengah masyarakat (efek pasca Pilkada).
Dilihat dari cara menggalang dukungan masyarakat, ada kecenderungan bahwa
kelompok-kelompok elit lokal yang mengusung proses pemekaran wilayah berusaha
menonjolkan isu marjinalisasi untuk memperoleh dukungan luas dari warga masyarakat.
Pemekaran wilayah dijual sebagai „panacea‟ untuk mengatasi hal itu. Rasa kebersamaan
dan rasa senasib sepenanggungan dari warga masyarakat di daerah calon pemekaran
biasanya dengan mudah dikristalisasikan untuk mendukung wacana pemekaran. Tetapi
isu itu biasanya segera hilang atau menguap ketika memasuki tahapan kedua, yaitu pada
tahapan pembenahan birokrasi dan pemilihan kepala daerah. Pada tahapan ini justru
kelompok elit yang tadi menggalang rasa kebersamaan dan senasib sepenangggungan
untuk mendukung pemekaran mulai „mengaduk-aduk‟ sentimen warga sehingga mereka
berhadap-hadapan untuk memenangkan calonnya dalam Pilkada6.
6 Pada tahapan ini, apa yang dicermati para ahli antropologi politik tampaknya benar, bahwa ketika manusia
berorganisasi untuk perjuangan politik, mereka sebenarnya tidak risau mengenai satuan sosial yang besar
melainkan bertindak menilai setinggi mungkin keuntungan bagi kelompok tempat mereka sangat berpihak
5
Pemekaran Wilayah di Sumatera Utara
Sumatera adalah satu dari 8 provinsi yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan
(1945). Pemekaran daerah pertama berlangsung pada tahun 1950, yaitu ketika Provinsi
Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi (Sumatera Utara termasuk didalamnya Aceh,
Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1957 Aceh menjadi provinsi sendiri
sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi seperti adanya
sekarang. Jauh sebelum merdeka, di wilayah Sumatera Utara pernah berdiri satu wilayah
keresidenan bernama Tapanuli (1915-1940), yang di kemudian hari (pasca Otda) ingin
kembali dihidupkan oleh beberapa pihak menjadi provinsi baru bernama Provinsi
Tapanuli.
Provinsi Sumatera Utara sampai dengan masa reformasi terdiri dari 11 kabupaten
(Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Tapanuli Utara,
Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Nias). Selain itu terdapat 6 kotamadya
yaitu Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Sibolga. Perlu
dicatat di sini bahwa Dairi pernah menjadi bahagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, dan
baru ditetapkan menjadi Kabupaten Dairi pada tahun 1964 melalui UU No. 15 Thn 1964
dan Perpu No. 4 Than 19647.
Berikut ini akan digambarkan secara garis besar fenomena pemekaran wilayah di
Sumatera Utara pasca reformasi, dengan memberikan perhatian khusus pada dua
tahapan pembentukan daerah otonom baru seperti disebutkan di atas, yaitu tahapan
penggalangan dukungan dan pengajuan usulan pemekaran dan tahapan pembenahan
birokrasi dan pemilihan kepala daerah. Pada bagian pertama akan diuraikan kasus
pemekaran kabupaten (yang sudah, sedang dan akan serta masih dalam wacana), dan
pada bagian kedua akan dibahas sedikit mengenai wacana pembentukan Provinsi
Tapanuli.
Pemekaran Kabupaten
Setelah reformasi telah bertambah sebanyak 7 kabupaten dan 1 kota baru di Sumatera
Utara. Tujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir,
Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Nias Selatan, Serdang Bedagai dan Samosir.
Kota yang dibentuk baru adalah Padang Sidimpuan, sebelumnya berstatus sebagai kotif
(kota administratif). Tabel di bawah ini menggambarkan daerah otonom baru di
Sumatera Utara setelah reformasi dan pemekaran yang sedang diproses, direncanakan
atau masih diwacanakan.
dan termasuk di dalamnya. Lihat Frank McClynn & Arthur Tuden (ed) “Pendekatan Antropologi pada
Perilaku Politik”, Penerbit UI-Press, Jakarta, 2000.
6
Tabel 1. Daerah otonom baru yang disahkan dan dlm proses pengajuan di Sumatera Utara
Kabupaten Pemekaran I Tahun Pemekaran II Tahun
Tapanuli Selatan 1. Mandailing Natal 23/11/98 Natal *) 2. Kota Padang Sidimpuan 21/06/01 3. Angkola Sipirok 4. Padang Lawas 5. Barumun Raya Tapanuli Utara 1. Toba Samosir 23/11/98 Samosir 18/12/03 2. Humbang Hasundutan 25/02/03 Dairi 1. Pakpak Bharat 25/02/03 Nias 1. Nias Selatan 25/02/03 Deli Serdang 1. Serdang Bedagai 18/12/03 Asahan 1. Batubara Labuhan Batu 1. Labuhan Batu Utara *) 2. Labuhan Batu Selatan *) Simalungun 1. Simalungun Atas *) 2. Simalungun Bawah *)
*) masih dalam wacana
Karakteristik daerah pemekaran:
1. Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelum dimekarkan merupakan kabupaten terluas di
Sumatera Utara. Dari segi sosial budaya dan demografi, wilayah ini dihuni oleh dua
kelompok etnik mayoritas dan dominan yaitu Mandailing dan Angkola. Karena itu,
latar pemekaran pertama yang dirancang sejak 1992 (masa Gubernur Raja Inal
Siregar) selain karena hamparan wilayah yang cukup luas serta potensi daerah
lainnya (faktor-faktor objektif sesuai syarat pemekaran wilayah) juga secara implisit
untuk mengakomodasi ruang politik bagi dua „daerah kebudayaan‟ yang dominan
yaitu Angkola (kabupaten induk) dan Mandailing (kabupaten pemekaran). Wacana
yang berkembang di Kabupaten Mandailing Natal saat ini untuk kembali
memekarkan wilayah menjadi dua, yaitu Mandailing dan Natal, juga terkait dengan
akomodasi „daerah kebudayaan‟ Natal yang berbudaya pesisir. Demikian halnya
proses pengusulan pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten
Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Barumun Raya (masih dalam proses di DPR RI),
kurang lebih juga dilakukan dengan menarik batas geografi budaya dalam varian
budaya Angkola.
2. Kabupaten Tapanuli Utara. Selain karena luas wilayah, pemekaran Kabupaten
Tapanuli Utara juga secara implisit diwarnai nuansa pemilahan batas geografi
budaya Batak Toba ke dalam varian Silindung (kabupaten induk), Toba (kabupaten
Toba Samosir), Humbang (kabupaten Humbang Hasundutan) dan Samosir
(kabupaten Samosir). Meskipun secara umum etnis Batak Toba terlihat memiliki
7 D.J. Padang Bth dalam “Pemekaran Kabupaten Dari Menjadi Dua Kabupaten Yakni Kabupaten Dairi dan
Kabupaten Pakpak Bharat”. Tulisan dalam buku Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah, diedit
oleh Wahyudi dkk. Penerbit The Asia Foundation & Yayasan Sada Ahmo, 2002.
7
identitas budaya yang sama dan homogen, sesungguhnya secara internal mereka
memiliki varian budaya yang kurang lebih kemudian diakomodasikan dalam batas-
batas wilayah administratif pemerintahan setelah pemekaran.
3. Kabupaten Dairi. Berbeda dengan dua kabupaten di atas, yang mana ditemukan
nuansa rivalitas etnik atau sub-etnik yang sama-sama kuat dalam kehidupan politik
dan ekonomi lokal, pemekaran Kabupaten Dairi (induk) menjadi Pakpak Bharat
(wilayah pemekaran) justru lebih dilandasi oleh adanya nuansa marjinalisasi
terhadap etnik „tuan rumah‟. Penduduk asli wilayah ini adalah etnis Pakpak, namun
dalam rentang sejarah yang panjang kedudukan mereka di dalam percaturan politik,
birokrasi, ekonomi dan sosial budaya justru tenggelam oleh dominasi Batak Toba di
daerah itu. Kutipan berikut ini agaknya cukup baik menggambarkan hal itu :
“besarnya keinginan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Dairi, khususnya di kalangan orang Pakpak lebih disebabkan oleh masalah ketidakadilan yang dirasakan sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, setelah kemerdekaan. Dari masa ke masa mereka merasa tidak diperhatikan, dinomorduakan dan dimarginalisasi, baik secara sistematis maupun non-sistematis”8.
4. Kabupaten Nias. Meskipun penduduk kabupaten Nias kecil, tapi wilayah mereka
terhampar luas di tepi Samudera Hindia dan terdiri dari kepulauan. Selain alasan
geografis, variabel budaya juga mewarnai penetapan batas-batas wilayah pemekaran
menjadi Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Kalau hanya alasan geografis, mungkin
yang lebih ideal adalah Kabupaten Nias (Pulau Nias) dan Kabupaten Kepulauan Batu.
Tetapi nuansa varian budaya Nias Utara dan Nias Selatan (dua episentrum
kebudayaan Nias) sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Nias, sehingga
pemekaran itu terkesan lebih mencerminkan rivalitas kedua varian budaya itu
ketimbang nuansa geografis.
5. Kabupaten Deli Serdang. Dari aspek demografis, kabupaten ini dihuni oleh beragam
kelompok etnis (masyarakat majemuk), namun ditilik dari sudut historis memiliki
dua episentrum kekuatan politik (kesultanan Deli dan Serdang). Ada beberapa
alternatif usulan yang pernah mencuat untuk pemekaran Deli Serdang, termasuk
wacana kabupaten Deli Hulu untuk mengakomodasi komunitas etnik Karo yang
cukup besar jumlahnya di wilayah ini. Namun akhirnya pemilahannya didasarkan
pada batas alam (bentangan Sungai Ular) dan batas geopolitik tradisional
(kesultanan Deli dan Serdang).
8 Lihat Lister Berutu dkk (2002) “ Pakpak dan Pemekaran Kabupaten Dairi”, dalam Wahyudi dkk (2002)
Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah. Penerbit The Asia Foundation dan Yayasan Sada
Ahmo.
8
Wacana pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi Simalungun Atas (mayoritas dihuni
oleh komunitas etnik asli Simalungun) dan Simalungun Bawah pernah mencuat ke
publik. Salah satu isu yang melekat di sana adalah marjinalisasi yang dihadapi oleh etnik
Simalungun yang „kalah bersaing‟ dengan dominasi politik dan ekonomi dari penduduk
lain, terutama Batak Toba.
Dari seluruh kasus pemekaran wilayah kabupaten yang sudah dan sedang
berjalan di Sumatera Utara, boleh dikatakan tidak ada kasus yang menimbulkan masalah
sosial yang serius, terutama atara warga masyarakat di kabupaten induk dan kabupaten
pemekaran. Tensi politik atau pertentangan justru banyak muncul di kalangan warga
masyarakat di wilayah yang akan dimekarkan, yaitu di seputar perebutan ibukota
kabupaten. Hal seperti ini muncul di Kabupaten Mandailing Natal (antara Kotanopan
dan Panyabungan) Kabupaten Pakpak Bharat ( antara Salak dan Sibande), Toba Samosir
(antara Balige dan Porsea). Persoalan yang rada unik muncul dalam kasus pemekaran
Kabupaten Tapanuli Selatan fase 2, yaitu Kabupaten Angkola Sipirok, Padang Lawas dan
Barumun Raya (masih dalam proses). Ketiga calon kabupaten pemekaran justru enggan
untuk dijadikan sebagai kabupaten induk. Satu faktor yang dominan dalam kasus-kasus
tersebut di atas adalah rivalitas antara komunitas-komunitas lokal yang didasarkan pada
ikatan sosio-kultural-politik-historis pra kemerdekaan.
Wacana Pembentukan Provinsi Tapanuli.
Berbeda dengan kasus pemekaran kabupaten yang tidak banyak mengalami hambatan,
kecuali karena faktor pelambatan yang sengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh pihak
pemegang otoritas administratif (DPRD, Bupati dan Gubernur), wacana pembentukan
Provinsi Tapanuli justru mendapat reaksi pro kontra di kalangan masyarakat Sumut.
Meski ide pemekaran Provinsi Sumatera Utara bukanlah sesuatu yang baru sama sekali9,
namun ide membentuk Provinsi Tapanuli mendapat penentangan dari sebagian besar
masyarakat Sumut. Gagasan awal Provinsi Tapanuli adalah di atas wilayah yang di
zaman kolonial disebut sebagai Keresidenan Tapanuli (1915-1940). Dalam batas wilayah
keresidenan di masa lampau itu termasuk wilayah Tapanuli Selatan sebelum pemekaran
(Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Pemko Padang Sidimpuan) sekarang.
Reaksi penolakan pertama datang dari masyarakat Mandailing dan Tapsel pada
umumnya. Penolakan itu bukan sesuatu yang baru, karena proyek membentuk Dewan
9 Basyral Hamidy Harahap mencatat bahwa pada tahun 1957 sudah pernah mengemuka gagasan pembagian
propinsi Sumut menjadi tiga propinsi. Salah satu cara pembagiannya dikemukakan oleh A.N.P.Situmorang
(anggota DPRD Sumut ketika itu), yaitu (1) propinsi gabungan dari Tapanuli Selatan, Labuhan Batu dan
Asahan; (2) gabungan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Simalungun, (3) gabungan dari Karo,
Deli Serdang, Langkat dan Medan. Lihat Basyral Hamidy Harahap dalam dokumen elektronik
http://www.basyral-hamidy-harahap.com/blog/index.php?.
9
Batak untuk wilayah Keresidenan Tapanuli juga gagal terutama karena penolakan orang
Mandailing untuk bergabung di dewan itu10.
Dalam wacana awal, bakal Provinsi Tapanuli itu akan meliputi 13 kabupaten/kota
yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir,
Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Dairi, Pakpak
Bharat, Pemko Padang Sidimpuan dan Pemko Sibolga. Karena reaksi penolakan yang
keras dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Pemko Padang Sidimpuan, maka
wacana yang berkembang kemudian adalah Provinsi Tapanuli dengan wilayah di atas
minus eks Tapanuli Selatan. Reaksi penolakan terus meluas, termasuk dari masyarakat
di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi, serta Nias.
Wacana paling mutakhir wilayah yang akan menjadi bakal provinsi Tapanuli itu adalah
eks Kabupaten Tapanuli Utara, yang dengan jumlah kabupaten saat ini (4) menurut UU
32 Thn 2004 belum memenuhi persyaratan fisik untuk menjadi sebuah provinsi.
Ada beragam alasan dan argumentasi bagi penolakan mereka untuk masuk dalam
rencana Provinsi Tapanuli itu. Berbagai diskusi dan seminar sudah banyak digelar,
media massa (cetak dan elektronik) gencar memberitakan wacana itu, situs-situs internet
dan blog-blog yang membahas rencana Protap juga tidak sedikit, baik menyuarakan yang
pro dan kontra terhadap rencana tersebut. Kalau ditarik benang merah dari alasan yang
menolak bergabung dalam Protap, kurang lebih adalah kekhawatiran yang kuat atas
pelanggengan hegemoni etnik Batak Toba terhadap etnik lain. Kekhawatiran itu cukup
beralasan mengingat prakarsa untuk membentuk provinsi baru ini justru didominasi
oleh elit-elit Batak Toba di perantauan, dan mereka mengklaim semua wilayah yang
direncanakan masuk dalam provinsi ini patut mendukung, termasuk atas alasan kultural.
Alasan kultural bahwa orang Mandailing berasal dari keturunan Si Raja Batak,
yang sangat teguh diyakini dan diklaim oleh orang Batak Toba tetapi juga tidak diyakini
dan sangat teguh ditolak oleh orang Mandailing, menurut hemat saya, adalah salah satu
urat akar masalah yang membuat kedua kelompok etnik ini tidak pernah bisa disatukan
dalam kerangka konsep Tapanuli ataupun Batak. Penolakan Pakpak Bharat dan Dairi
untuk Protap harus dilihat dari pengalaman historis yang panjang mereka alami di
bawah hegemoni Batak Toba secara politik, ekonomi, religi dan kultural. Salah satu
wacana penolakan yang pernah mengemuka, mereka lebih baik memilih tetap di dalam
wilayah Propinsi Sumut, atau akan membentuk propinsi sendiri, atau bergabung dengan
10
Disertasi Lance Castles yang kini dibukukan dan diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia di bawah judul
“Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940” oleh KPG (2001), secara detil
menggambarkan betapa proyek menyatukan Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan tidak realistis dan tidak
akan berhasil.
10
Aceh Singkil dan Alas. Adanya penolakan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah juga
dilandasi oleh alasan kultural11.
Kembali ke pangkal pembahasan tentang pemekaran wilayah, saya sendiri punya
pendapat bahwa pemekaran wilayah adalah sesuatu yang wajar dan baik dilakukan.
Secara objektif, pemekaran wilayah akan mempersingkat jarak pelayanan publik, akan
mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan juga akan
memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk ikut mengontrol
pelaksanaan pemerintahan. Idealnya, pemekaran wilayah akan menumbuhkan ide-ide
kreatif baru dalam mengembangkan potensi daerah, dan dalam banyak kasus hal itu
sudah terbukti12. Singkat kata, gagasan dasar dari pemekaran wilayah adalah bagian yang
harus menyatu dengan kebijakan desentralisasi. Persoalannya adalah kebijaksanaan
warga masyarakat dan pemerintah dalam menentukan batas-batas wilayah pemekaran,
yang harus benar-benar memperhatikan aspek sosial budaya. Fakta menunjukkan bahwa
faktor politik yang kait mengait dengan faktor sosial budaya (etnisitas) cukup dominan
dalam gerakan pemekaran wilayah13.
Kumbang-kumbang dalam Daerah Otonomi Baru
Ketika sebuah daerah otonom baru terbentuk sebagai hasil dari perjuangan bersama
sebagian besar komponen masyarakat yang mengajukannya, untuk sebagian besar kasus,
persoalan baru segera muncul. Siapa yang akan menjadi „pilot‟ untuk menerbangkan
„pesawat‟ kabupaten baru itu ? Apa yang ada di pikiran pilot dan segenap kru-nya ? Nah,
secara prosedur formal sesuai aturan perundang-undangan, pilot akan dipilih melalui
11
Sekedar untuk contoh, salah satu opini menolak Provinsi Tapanuli ditulis di situs Waspada Online tanggal
4 April 2007, dari seorang warga bernama Rusli Siburian/Sekretaris Umum Ikatan Masyarakat Tapanuli
Tengah/Sibolga. Salah satu butir (8) pernyataannya dikutip di dini sbb : “Dengan bergabungnya Kota
Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah ke dalam Propinsi Tapanuli akan merupakan kemunduran, karena
lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, khususnya untuk kesejahteraan kehidupan rakyat.
Pembentukan Propinsi Tapanuli hanya untuk kepentingan segelintir orang dari salah satu etnis yang haus
akan „jabatan dan kekuasaan‟”., Menarik pula untuk mengutip pernyataannya pada butir 9 yang berbunyi:
“Kalau Panitia Pemrakarsa ingin memekarkan kampung halamannya Tapanuli menjadi PropinsiTapanuli,
silahkan. Akan tetapi jangan memaksakan kehendak agar Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah
bergabung ke dalamnya. Karena Kota Sibolga dan TapanuliTengah adalah kampung halaman kami
masyarakat pesisir, yang juga kampung halamannya Bapak Jenderal TNI (Purn) Feisal Tanjung, Bapak Ir.
Akbar Tanjung, Bapak Mayjen Pol (Purn) Salim Siregar dan lain-lainnya”. 12
Marzuki Usman (2005) dalam salah satu tulisannya yang diakses dari situs elektronik
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/keuangan/2005/0411/keu3.html berjudul Dampak Positif dari
Pemekaran Wilayah, antara lain memaparkan pengamatannya tentang dampak positif pemekaran wilayah di
Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Tentang Sumatera Utara bahkan ia mempunyai pendapat sebaiknya
dibagi menjadi tiga propinsi, yaitu (a) Propinsi Sumatera Timur dengan ibukota Medan, (b) Propinsi
Tapanuli dengan ibukota Sibolga, dan (c) Propinsi Mandailing Angkola dengan ibukota Padang Sidimpuan.
Salah satu pernyataannya berbunyi : “…(saya) mengakui akan kesalahan saya yang semula memandang
sinis kepada usaha pemekaran wilayah. Rupanya memang diperlukan pemekaran wilayah untuk
menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru”. 13
Dokumen RPJMN 2004-2009 mengungkapkan fakta bahwa dalam pelaksanaannya proses pembentukan
daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan aspek politis, kemauan sebagian kecil elit daerah, dan
belum mempertimbangkan aspek-aspek lain selain yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah yang ada.
11
pemilihan kepala daerah secara langsung. Anggota DPRD juga akan diisi dengan orang-
orang pilihan hasil Pemilu legislatif. Perangkat daerah akan diisi oleh orang-orang yang,
sayangnya, dipertimbangkan secara subjektif oleh sang pilot. Pengelolaan pemerintahan
kemudian berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan aturan-aturan formal yang berlaku.
Sampai pada tahapan ini, isu-isu yang mengemuka antara lain adalah keharusan
untuk mendudukkan „putra daerah‟ sebagai pilot. Faktanya, seringkali pula yang
menjelma sebagai putra daerah ini adalah elit-elit politik atau elit-alit ekonomi yang dari
awal aktif menghela gerakan atau perjuangan pemekaran wilayah. Tak bisa dipungkiri
kini bahwa akses untuk menduduki jabatan politik tertinggi di kabupaten baru maupun
kabupaten induk, adalah mereka yang didefinisikan sebagai putra daerah. Bagaimana
mendefinisikan putra daerah? Eef Saefullah Fatah14 mengenalkan 4 kategori putra
daerah yang ia sebut sebagai (a) putra daerah genealogis, (b) putra daerah politik, (c)
putra daerah ekonomi, dan (d) putra daerah sosiologis. Menurut Eef, secara teoritis,
seorang putra daerah sosiologis lah yang berpotensi memiliki ikatan emosional paling
tinggi dan memahami persoalan mendasar di daerahnya. Hanya saja dalam kenyataan,
kategori ini jarang terpilih dalam Pilkada, karena tak memiliki kapasitas ekonomi dan
akses politik yang memadai untuk masuk ke arena itu. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa untuk maju sebagai bakal calon bupati harus bertransaksi dengan partai politik
yang akan mengusung calon dalam Pilkada, karena aturannya memang mengharuskan
pencalonan lewat partai politik15.
Menurut hemat saya, di sinilah ironi pertama dari pemekaran wilayah. Bukan
proses pemekarannya yang patut dipersalahkan, tetapi perangkat lunak sistem hukum
yang mengatur pengambilan keputusan untuk jabatan politik tersebut membuka peluang
sedemikian rupa sehingga yang terpilih adalah kumbang-kumbang yang hanya doyan
mengisap sari bunga. Ketika pertanyaan “apakah dengan pemekaran wilayah sudah
tercapai tujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat”?, dengan gampang
terjawab dan dijawab oleh masyarakat : tidak, atau masih jauh panggang dari api.
Masyarakat yang di awal secara massif mendukung ide dan usulan pemekaran pun
segera dilupakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan
di wilayah baru. Jika ketika penggalangan dukungan dibuat seminar, kongres rakyat,
musyawarah besar, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, membuat surat pernyataan
dukungan, dan seterusnya; setelah pemekaran suara mereka tidak didengarkan lagi.
Ironi berikutnya sebagai akibat dari keperluan transaksi politik yang tidak murah
itu, ialah keperluan untuk menghela gerbong pendukung yang lazim disebut TS ke dalam
14
Lihat Eef Saefulloh Fatah (2005), “Putra Daerah”, dalam Kolom Pilkada Eef Saefullah Fatah, situs
Tempo Interaktif, Senin 18 April 2005. 15
Antara adadan tiada sebagai bukti faktual, wacana yang selalu berkembang ketika Pilkada akan
berlangsung adalah keharusan „membeli perahu‟ partai politik yang nilainya milyaran.
12
„ajang‟ penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk jabatan di birokrasi,
pemborong, dan cara-cara partisipasi lainnya. Hal ini kemudian membentuk polarisasi
baru di daerah, dan sayangnya dalam iklim negeri kita yang masih kental aroma KKN,
akan menjadi investasi negatif bagi upaya pembangunan daerah untuk mencapai tujuan
semula “menyejahterakan kehidupan masyarakat”. Ironi lainnya, persaingan dalam
merebut jabatan politik sebagai bupati –yang dihela dengan memobilisasi pendukung
atau massa yang tidak rasional (memanipulasi basis dukungan etnik dan klen, kampung,
dan basis-basis primordial lainnya), kemudian tidak selesai pasca Pilkada. Kultur yang
tetap kuat di tengah masyarakat kita adalah kultur „bertarung‟, bukan „berkompetisi‟,
sehingga pihak yang kalah harus menerima kekalahannya secara mutlak. Akibatnya,
tersimpan potensi konflik di tengah masyarakat karena terjadinya fragmentasi sosial
yang dihela oleh para TS kandidat bupati. Pertarungan serupa akan diulangi lima tahun
ke depan, dan siklus yang sama akan berulang.
Penutup
Menurut hemat saya, aspek negatif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti
digambarkan di atas bukan hanya berlaku di daerah pemekaran baru, tetapi juga berlaku
di semua daerah setelah kebijakan Pilkada langsung. Hal itu terjadi lebih karena kita
baru menjalankan demokrasi secara formal (hanya mengadopsi perangkat keras
demokrasi), belum menjalankan demokrasi secara substantif. Karena itu, masalahnya
bukan berpangkal pada proses pemekaran melainkan pada perangkat lunak (sistem)
hukum kita yang mengatur otonomi. Perangkat lunak tersebut sejauh ini belum atau
sama sekali tidak mengakomodasikan potensi kultural yang pernah dikembangkan oleh
masyarakat kita tempo dulu. Mungkin hal ini terjadi karena bangsa kita telah menempuh
evolusinya secara tidak taat azas sebagaimana disebutkan oleh Budi Baik Siregar dkk
(2002), yang lebih menggagas kembalinya kita ke konsep otonomi masyarakat asli16.
Andaikata pun kita tidak berhasrat untuk kembali ke konsep otonomi masyarakat
asli (dengan menggali khasanah budaya demokrasi kita yang pernah ada), dan kita tetap
konsisten dengan sistem demokrasi yang diadopsi dari Barat, maka seyogianya kita juga
harus mengadopsinya secara utuh, termasuk aspek substantif dari demokrasi itu, yaitu
ruh penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip dasar “good
governance”. Untuk banyak hal, akan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik itu juga sudah diatur sedemikian rupa dalam kultur
otonomi masyarakat asli. Menurut hemat saya, akan sangat bijaksana jika seandainya
dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran wilayah (yang notabene basis
16
Lihat Budi Baik Siregar dkk (ed) “ Kembali Ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli”;
diterbitkan oleh FPPM, Jakarta.
13
utama penarik batas geografisnya adalah batas-batas pusat kebudayaan di masa lalu)
juga dimungkinkan untuk mengakomodasikan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai untuk
membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Yang selama
ini terjadi, sejauh amatan saya, adalah kelaziman menggunakan basis etnisitas dan
kebudayaan sebagai ramuan untuk tujuan politik (oleh elit-elit politik lokal), kemudian
menggunakan sistem hukum formal untuk mencapai tujuan (jangka pendek) --termasuk
untuk mengelak dari tanggung jawab jika tujuan tidak tercapai, lalu meninggalkan basis
dukungan awal untuk mencapai tujuan pragmatis (individual atau kelompok). Amatan
saya boleh jadi benar, boleh jadi pula salah. Mari berdiskusi. ***