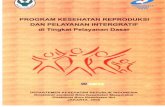fungsi ritual tari ngayau dalam upacara nyobeng suku dayak ...
MEMAHAMI ESSENTIAL MESSAGES UPACARA TRADISIONAL MELALUI PEMBELAJARAN SOSIOLOGI INTEGRATIF* Oleh
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of MEMAHAMI ESSENTIAL MESSAGES UPACARA TRADISIONAL MELALUI PEMBELAJARAN SOSIOLOGI INTEGRATIF* Oleh
MEMAHAMI ESSENTIAL MESSAGES UPACARA TRADISIONAL
MELALUI PEMBELAJARAN SOSIOLOGI INTEGRATIF*
Oleh:
Zulkarnaen Syri Lokesywara**
Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah
Guru SMA Negeri 1 Jatinom-Kabupaten Klaten
Dipresentasikan pada International Graduate Student Conference (IGSC) di Sekolah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 1-2 Desember 2009
MEMAHAMI ESSENTIAL MESSAGES UPACARA TRADISIONAL
MELALUI PEMBELAJARAN SOSIOLOGI INTEGRATIF*
Zulkarnaen Syri Lokesywara**
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas yang sangat
tinggi, baik dari segi agama, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Menurut
Zulyani Hidayah (1999: 284) jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 565 yang
tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di antara berbagai suku bangsa di Indonesia,
suku bangsa Jawa jumlah populasinya paling banyak dengan mayoritas agama yang
dianut adalah Islam. Meski begitu, Islam yang berkembang dan dianut oleh suku
bangsa Jawa banyak dipengaruhi oleh unsur agama lain, terutama Hindu. Selain itu,
strategi dakwah para Wali di Jawa yang menghindari konfrontasi secara frontal
menjadi salah satu penyebab begitu kuatnya pengaruh Hindu dalam keislaman
masyarakat Jawa.
Masyarakat Jawa percaya adanya kekuatan adikodrati yang disebut kasekten
(kesaktian) serta percaya bahwa roh-roh para leluhur dan roh-roh alam sangat
berpengaruh dalam kehidupan manusia. Clifford Geertz (dalam James Danandjaja,
1991: 158) membagi makhluk-makhluk gaib di Jawa Tengah menjadi beberapa
golongan, yaitu memedi (makhluk gaib yang menakutkan), lelembut (makhluk gaib
yang dapat memasuki tubuh kasar manusia), thuyul (makhluk gaib yang dapat
diperbudak manusia, dhemit (makhluk gaib setempat), dan danyang (makhluk gaib
penjaga keselamatan seseorang). Makhluk-makhluk halus tersebut menempati
lingkungan di sekitar tempat tinggal manusia dan selain dipercaya dapat
mendatangkan sukses dalam usaha, kebahagiaan, kewibawaan, kekayaan, ataupun
keselamatan, makhluk halus juga diyakini dapat menimbulkan gangguan dalam
kehidupan manusia. Untuk itu, agar terhindar dari gangguan makhluk halus, manusia
harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi alam sekitarnya dengan cara berpuasa,
berpantang makanan dan perbuatan tertentu, menyiapkan sesaji, atau melakukan
selamatan. Meskipun keyakinan tersebut tidak ilmiah, menurut Brundvand aspek
kepercayaan dan perbuatan takhayul sangat luas persebarannya di semua lapisan
masyarakat (James Danandjaja, 1991: 155).
Selamatan (Jawa: selametan) adalah suatu upacara makan bersama makanan
yang telah diberi doa oleh modin (orang yang dianggap lebih menguasai ajaran
Islam) sebelum dibagi-bagikan (Kodiran dalam Koentjaraningrat, 1999: 347). Tujuan
inti upacara selametan adalah untuk menghormati, mensyukuri, memuja, dan
memohon keselamatan kepada Tuhan melalui makhluk halus, arwah leluhur, atau
arwah orang-orang tertentu. Bagi sebagian besar Jawa Santri, upacara-upacara
tradisional yang diselenggarakan masyarakat Jawa dikategorikan perbuatan musyrik
atau menyekutukan Tuhan. Penelitian Sugianto di Kalipang (Blitar) terhadap Ritual
Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah pun menegaskan hal itu. Meskipun sebagian
besar masyarakat Kalurahan Kalipang adalah penganut faham Ahlussunah wal
Jamaah, mereka tidak dapat meninggalkan tradisi yang telah berjalan bertahun-tahun
tersebut (http://202.159.18.43/jsi/131sugianto.htm). Terhadap ritual tersebut, hanya
sebagian kecil masyarakat Kalipang menganggap sebagai hal yang musyrik.
Beberapa upacara tradisional yang dilakukan dalam hubungannya dengan
kematian adalah surtanah, nelung ndina, mitung ndina, matang puluh dina, nyatus,
mendhak pisan, mendhak pindho, nyewu, dan nyadran. Meskipun secara kuantitatif
tidak tercatat, para santri (menurut kategorisasi dari Geertz) memandang upacara-
upacara tradisional tersebut sebagai perbuatan musyrik. Sikap memvonis seperti itu
tentu saja sangat tidak bijaksana, karena menimbulkan perasaan saling curiga bahkan
dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya. Begitu pula kondisi yang terjadi di kalangan siswa SMAN
1 Jatinom, sebuah kecamatan yang dikenal sebagai salah satu basis Muhammadiyah
yang kuat di kabupaten Klaten.
B. Permasalahan
Dari uraian latar belakang semacam itulah muncul beberapa masalah yang
perlu dicarikan solusinya. Terdapat tiga masalah pokok yang muncul, yaitu:
a. Mengapa muncul suasana saling curiga di antara komponen bangsa,
khususnya di antara para siswa?
b. Bagaimana menghilangkan sikap saling curiga di antara warga masyarakat,
khususnya para siswa agar tidak terjadi disintegrasi di antara mereka?
c. Bagaimana sekolah sebagai sebuah institusi ilmiah mampu berperan
mereduksi suasana saling menyalahkan dan sekaligus menciptakan suasana
pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan intelektual siswa?
C. Tujuan Penulisan
Penelitian sederhana ini berusaha mencari akar masalah munculnya suasana
saling menyalahkan di antara umat Islam, khususnya warga sekolah di SMAN 1
Jatinom, dalam menyikapi pelaksanaan upacara-upacara tradisional yang
dilaksanakan masyarakat, untuk kemudian mencoba menemukan usaha-usaha yang
dapat dilakukan untuk mencegah munculnya suasana saling menyalahkan tersebut.
Sekolah, sebagai salah satu tempat bagi terjadinya transfer nilai dan norma,
mempunyai posisi strategis bagi upaya tersebut. Untuk itu sekolah harus mampu
menemukan perannya dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif dalam
menyikapi pelaksanaan upacara-upacara tradisional yang dilaksanakan masyarakat.
II. Kajian Literatur
A. Islamisasi Jawa
1. Metode Dakwah Para Wali
Sebagai agama baru di Jawa saat itu, Islam menarik banyak simpati dari
penduduk, terutama golongan menengah, kaum pedagang, dan buruh di bandar-
bandar (H.J. de Graaf dan TH. G. TH. Pigeaud, 1986: 24). Rasa persaudaraan dalam
agama antarbangsa itu, yang pada asasnya tidak mengakui adanya perbedaan
keturunan, golongan, dan suku di antara para pemeluknya, ternyata mempunyai daya
tarik bagi para pedagang dan pelaut, yang berbeda-beda tempat asalnya dan
mempunyai berbagai adat-istiadat dan cara hidup.
Dalam buku “Mengislamkan Tanah Jawa”, Widji Saksono (1995: 87-94)
mengemukakan beberapa metode dakwah para wali dalam penyebaran agama Islam.
Metode-metode yang digunakan adalah:
a. Metode maw’izhatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan
Metode dakwah ini merujuk pada Al Quran Surat An Nahl ayat 125:
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapapat petunjuk.
Maw’izhatul hasanah diterapkan dalam dakwah kepada para tokoh khusus (penguasa
dan kerabatnya) dengan pendekatan personal. Kepada mereka diberikan keterangan,
pemahaman, dan permenungan (tadzkir) tentang Islam, peringatan-peringatan
dengan bahasa yang halus, dan bertukar pikiran dari hati ke hati dalam suasana
penuh toleransi dari pihak wali terhadap pendapat dan keyakinan para tokoh
masyarakat. Dengan metode ini, Adipati Aria Damar dari Palembang bersedia masuk
Islam bersama istri dan diikuti oleh sebagian besar rakyatnya setelah beliau
berdiskusi panjang dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Demikian juga halnya
ketika beliau berdakwah terhadap Prabu Brawijaya Kertawijaya dari Majapahit.
Mendengar wejangan yang demikian bagus dari Sunan Ampel, sangat sulit hati
Prabu Brawijaya untuk menolak. Tetapi karena beliau berkedudukan sebagai raja,
banyak pertimbangan yang membuatnya tidak mudah begitu saja menerima pendapat
dan saran orang lain, terutama dalam hal keagamaan. Sebagai raja, ia terikat oleh
adat kebiasaan kerajaan dan tradisi-tradisi rakyatnya yang secara konvensional tidak
dapat diabaikan begitu saja, sehingga dengan berbagai cara beliau tetap menolak
dengan halus ajakan masuk Islam. Terhadap permaisurinya, Prabu Brawijaya tidak
keberatan jika berkehendak memeluk Islam. Apabila metode maw’aizhatul hasanah
tidak berhasil, barulah para wali menempuh jalan lain yaitu al-mujadalah billati hiya
ahsan. Cara ini diterapkan terutama terhadap tokoh yang secara terang-terangan
menunjukkan sikap permusuhan terhadap Islam.
Metode serupa dipergunakan pula oleh Sunan Kalijaga ketika berdakwah
mengajak Adipati Pandanarang di Semarang. Awalnya terjadi perdebatan sengit,
tetapi berakhir dengan masuknya Adipati ke dalam Islam, karena sangat terkesan
dengan anjuran dan kesopanan Sunan Kalijaga. Demikian terkesannya Adipati
sampai-sampai beliau rela meninggalkan kedudukannya untuk dapat diterima
sebagai murid Sunan Kalijaga
b. Metode Al-Hikmah
Metode al-hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali merupakan
jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional.
Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam secara massal.
Sunan Kalijaga mengusulkan diadakan keramaian Sekaten (Syahadatayn) yang
diadakan di Masjid Agung menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dengan memukul gamelan yang sangat unik dalam hal langgam lagu maupun
komposisi instrumental yang telah lazim, Sunan Kalijaga berhasil mengumpulkan
massa untuk kemudian diberikan dakwah keislaman. Selain itu, Sunan Kalijaga juga
mengarang lakon (ceritera) wayang baru dan menyelenggarakan pergelaran-
pergelaran wayang yang sangat digemari pada saat itu. Sebagai upah mendalang,
Sunan Kalijaga meminta Kalimat Syahadat. Dengan Kalimat Syahadat beliau baru
mau dipanggil untuk memainkan suatu lakon wayang yang biasanya diselenggarakan
dalam rangka meramaikan pesta atau upacara peringatan.
Untuk maksud yang sama, Sunan Kudus mengikat seekor lembu yang dihias
istimewa di halaman dalam masjid, sehingga masyarakat yang ketika itu masih
memeluk agama Hindu datang berduyun-duyun menyaksikan lembu yang
diperlakukan istimewa itu. Bagi masyarakat Hindu, lembu merupakan binatang
istimewa karena menjadi tunggangan dewa. Sesudah massa terkumpul di sekitar
masjid, Sunan Kudus lalu menyampaikan dakwahnya. Menyaksikan lembu tidak
dihinakan oleh Sunan Kudus, minat dan simpati masyarakat penganut Hindu
terhadap Islam muncul, sehingga secara sukarela menyatakan diri masuk Islam.
Bahkan sampai saat ini, masyarakat Demak dan Kudus tidak terbiasa makan daging
sapi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa makan daging kerbau untuk
membuat empal, sate, ataupun soto.
c. Metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah
Sebagai agama baru, pada saat itu tingkat pemahaman masyarakat terhadap
Islam sangat variatif. Agar ajaran Islam dapat dimengerti dan akhirnya dijalankan
oleh masyarakat secara merata, para wali menggunakan metode dakwah yang
didasarkan atas pokok pikiran li kulli maqam maqal, artinya ada tingkatan-tingkatan
yang berbeda, sehingga perlu perlakuan yang berbeda pula. Sesuai dengan cara ini,
penyampaian fiqih ditujukan terutama bagi masyarakat awam dengan jalan pesantren
dan melalui lembaga sosial.
Dalam lingkungan pesantren disediakan pengajaran dan pendidikan bagi
masyarakat umum yang ingin belajar takhassus (mengkaji secara intens) masalah-
masalah fikih dan syariat. Untuk menjadi pesertanya, tidak diajukan syarat-syarat
khusus karena memang dibuka untuk masyarakat yang berminat. Nilai-nilai
ketauhidan disampaikan kepada masyarakat awam melalui ceritera-ceritera wayang
yang sudah lekat dalam kehidupan masyarakat, seperti lakon Dewa Ruci dan Jimat
Kalimasada, serta dikarang pula kitab bacaan umum seperti Kitab Ambiya (Kitab Al
Anbiya) yang bercerita tentang riwayat para nabi. Ilmu Kalam atau Tauhid
disampaikan sebagai ta’lim atau pengajaran melalui pesantren, dan diberikan secara
terbatas kepada orang-orang khawas. Selanjutnya, ushul suluk (tasawuf) disampaikan
melalui wirid, yaitu pengajaran dengan wejangan secara tertutup dan sangat
eksklusif. Cara ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang telah
mempunyai lemek atau dasar pengetahuan Islam sebelumnya. Hal itu dilakukan
untuk menghindari terjadinya kekeliruan, salah pengertian, dan salah penggunaan
ilmu ini.
2. Dampak Metode Dakwah Walisongo
Metode dakwah para wali dalam upaya mengislamkan orang-orang Jawa
dapat dikatakan sangat sukses. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari faktor intern
yang ada pada diri para wali. Mereka berpegang teguh pada dasar musyawarah,
menghormati kemerdekaan berpikir dan berinisiatif, toleran, dan ihsan. Hal ini sesuai
dengan pegangan dan busana mereka, yaitu baju takwa antakusuma langsarane jeng
Nabi (Widji Saksono, 1995: 131). Baju takwa adalah baju dengan model (potongan)
mirip baju surjan dengan kancing baju berjumlah lima dan enam yang
melambangkan Rukun Islam dan Rukun Iman, sedangkan antakusuma berarti
kebaikan yang tidak terbatas (anta: tidak terbilang, kusuma: baik, mulia, harum,
bunga) sebagai perlambang ihsan (kebajikan dan kebijaksanaan) sebagai buah dari
takwa.
Faktor ekstern yang mendukung sukses para wali adalah karakter ajaran
Islam yang mereka siarkan. Banyak unsur Islam yang memiliki kesamaan dan
kesesuaian dengan unsur Indonesia asli sebelum Hindu-Bhuda. Selain itu, Islam
telah membuktikan dirinya sebagai agama universal, artinya mampu bermanifestasi
dalam kebudayaan mana pun.
Faktor ekstern lainnya yang mendukung kesuksesan wali bersumber dari
situasi dan susunan masyarakat pada zaman itu. Masa perjuangan para wali
bersamaan dengan masa kekacauan kerajaan Majapahit karena kondisi ekonomi dan
poltiknya saat itu. Masyarakat mulai gelisah dan rindu perubahan. Kerinduan itulah
yang dapat dipenuhi oleh Walisongo yang membawa Islam sebagai alat
pembaharuan. Syiwa dan Bhudisme yang pandangannya pesimis terhadap dunia
pada dasarnya bertentangan dengan alam pikiran orang Jawa saat itu. Ditambah lagi
susunan kedua agama lama tersebut yang piramidal-kastaistis tidak menggembirakan
para rakyat, karena mereka tidak dapat dapat menduduki posisi-posisi sentral yang
dikuasai Hindu-Feodal-Biksu Bhuda (Atmodarminto dalam Widji Saksono, 1995:
224). Kedatangan Islam dipandang sebagai sebuah pencerahan, karena adanya titik
persamaan berupa dasar ketauhidan, prinsip musyawarah, gotong-royong,
kesetaraan, dan sebagainya. Jika dahulu orang menitikberatkan alam pikirannya
kepada keajaiban dan kegaiban sesuai aliran Tantrayana, maka hal ini dapat dijumpai
pula dalam tasawuf Islam yang dalam perkembangannya banyak memperoleh corak
panteisme. Tasawuf inilah yang membuka lebar hati masyarakat. Kehadiran Islam
bersama tasawuf dijadikan sebagai jalan baru dalam alam pikiran lama yang
mencita-citakan moksa. Dua kalimat Syahadat untuk menjadikan seseorang menjadi
Islam, dengan mudah diucapkan dan diresapkan tanpa suatu pertentangan batin
(Soekmono dalam Widji Saksono, 1995: 226).
Namun, dilihat dari sudut pandang keberagamaannya, mereka
memperlihatkan kuantitas yang luas dan kualitas beragama yang dangkal.
Keberagamaan mereka dipenuhi dengan bid’ah akibat sinkretisme unsur Jawa-
Hindu-Bhuda. Dampak metode pengislaman yang lebih dominan kesufiannya adalah
masyarakat Jawa sangat memperhatikan mistik tetapi kurang memperhatikan
syariatnya. Selain itu, menurut Siswoharsojo, piwulang ingkang mboten ngeblak
(cara memberikan pengetahuan agama yang tidak tegas atau tidak terang-
terangan/gamblang) melalui wayang, sekaten, kidung (nyanyian khas Jawa), dan
cara mengubah struktur lama dari animisme-Hindu-Bhuda yang tidak revolusioner
tetapi reformis bahkan revisioner, menimbulkan corak keislaman tersendiri yang
cenderung menyimpang dari aslinya. Corak keislaman tersebut setelah meluas dan
berkembang dalam masyarakat sulit diatasi dan dibakukan (institutionalized) dalam
kehidupan masyarakat sampai sekarang. Upacara-upacara yang berhubungan dengan
kematian pada masyarakat Jawa merupakan contoh munculnya penyimpangan fikih
Islam, seperti surtanah, nelung ndina, matang puluh dina, nyatus, mendhak pisan,
mendhak pindho, nyewu, dan nyadran.
Mengacu pada Serat Kadilangu dan Serat Walisanga, Koentjaraningrat
(1984: 336-338) mengemukakan bahwa makhluk hidup terdiri dari tubuh jasmaninya
(selira) dan semua keinginan yang ada pada dirinya (kamarupa). Jasmani dapat
hidup dan bergerak karena ada atma (semangat), kama (keinginan), dan prana
(nafsu). Berbeda dengan makhluk lain, manusia juga mempunyai manas (akal),
menasa (kecerdasan), dan jiwa. Apabila manusia mati, atma, kama, prana, manas,
dan jiwa meninggalkan jasmaninya pada hari ke-3 setelah kematiannya. Pada hari
ke-7, rohnya masih memiliki keinginan, dibimbing oleh malaikat ke kamaloka
menuju ke gerbang melewati jembatan shirotal mustakim yang lebarnya sepertujuh
belah rambut wanita. Bila tidak berhasil melewati, ia akan jatuh ke neraka dan jika
terlalu banyak dosa ia akan terperosok lebih dalam lagi ke bumi kapindho (bumi
kedua) yang berisi magma pijar. Dalam waktu lama ia akan dilahirkan kembali
sebagai seekor binatang. Kemudian masuk bumi ketiga dan dilahirkan kembali
sebagai tanaman, dan akhirnya dilahirkan kembali sebagai manusia agar hidup lebih
baik dan berguna. Roh akan berada di kamaloka sampai hari ke-40. Pada hari ke-100
masuk ke dewaka (surga pertama), kemudian mati ke dua kalinya. Tubuh halusnya
yang berisikan sisa-sisa nafsu dan keinginan ditinggalkan. Apabila keluarga yang
ditinggalkan masih memanggilnya, maka roh menjadi lelembut (makhluk halus) dan
berkeliaran di sekitar tempat tinggal manusia dan menetap di sekitar kaum keluarga
sebagai roh penjaga. Ia akan bersemayam di pohon besar, batu, gua, atau daerah
perbukitan (www.petra.ac.id). Roh yang berhasil masuk surga pertama akan menjadi
lebih murni. Pada hari ke-1000 ia akan masuk surga kedua. Proses ini akan berulang
hingga roh masuk ke surga ke tujuh dan mencapai moksa (kesempurnaan).
Upacara tradisonal yang berhubungan dengan kematian yang dilaksanakan
masyarakat Jawa adalah:
a. Surtanah
Poerwadarminta (dalam Mulyadi dkk., 1984: 56) mengemukakan bahwa
surtanah berasal dari kata dalam bahasa Jawa ngesur tanah yang berarti melakukan
selamatan terhadap orang yang baru saja meninggal dunia. Dilaksanakan pada hari
pemakaman jenasah setelah para pelayat pulang dari kuburan.
Ubarampe atau perlengkapan dan materi dalam upacara surtanah adalah sega
golong (nasi dibentuk bola), sega asahan (nasi putih yang ditaruh di atas nyiru),
tumpeng pungkur (nasi dibentuk gunungan/kerucut), sega wudhuk (nasinasi gurih),
ingkung (ayam jantan masak utuh), tumpeng wajar (nasi putih tanpa lauk berbentuk
kerucut), kembang rasulan (bunga Rosul yang terdiri dari mawar, melati, dan
kenanga), bubur abang putih (bubur yang diberi cairan gula kelapa dan bubur biasa),
tukon pasar (materi selamatan berupa segala macam buah), wajib ( uang yang
diberikan kepada pemimpin upacara), dan dupa (kemenyan) yang dibakar sebelum
upacara dilangsungkan. Semua materi tersebut diletakkan di suatu tempat kemudian
dikepungke (dikepung) oleh hadirin. Kegiatan ini disebut kenduren atau kepungan.
Acara ditutup dengan doa berbahasa Arab dipimpin oleh kaum.
Di samping kenduren, selamatan surtanah juga diikuti dengan penyiapan
sesajen. Sesajen ini dibuang ke tempat-tempat yang dianggap angker, misalnya
perempatan jalan, pojok desa, pohon besar, dan sebagainya
b. Nelung ndina
Upacara ini dilaksanakan tepat tiga (Jawa: telu) hari setelah kematian seseorang.
Materi untuk selamatan hampir sama dengan surtanah, tetapi tanpa tumpeng pungkur
beserta lauk-pauknya. Pada upacara ini ditambah dengan takir pontang, yaitu wadah
dari daun pisang dan daun kelapa yang masih muda berisi nasi putih dan nasi punar
(kuning). Penggunaan sesajen sama dengan surtanah.
c. Mitung ndina
Upacara ini dilaksanakan tepat tujuh (Jawa: pitu) hari setelah kematian
seseorang. Materi untuk selamatan hampir sama dengan surtanah, tetapi ditambah
dengan apem ketan kolak. Penggunaan sesajen masih sama dengan kedua selamatan
di atas.
d. Matang puluh dina
Upacara selamatan ini dilaksanakan tepat empat puluh hari (Jawa: patang puluh)
setelah kematian seseorang. Materi atau perlengkapan untuk selamatan hampir sama
dengan mitung ndina. Hanya saja materi berupa ingkung ayam diusahakan dari ayam
berbulu putih mulus. Sulitnya mendapatkan ayam berbulu putih mulus menyebabkan
masyarakat mengganti dengan ayam berbulu biasa. Penggunaan sesajen sama dengan
surtanah.
e. Nyatus dina
Dilaksanakan tepat seratus hari (Jawa: satus) setelah kematian seseorang. Materi
dan sesajen untuk selamatan sama dengan selamatan yang telah dilaksanakan.
f. Mendhak pisan
Dilaksanakan tepat setahun setelah kematian seseorang. Materi dan sesajen untuk
selamatan sama dengan selamatan yang telah dilaksanakan.
g. Mendhak pindho
Dilaksanakan tepat dua tahun setelah kematian seseorang. Materi dan sesajen
untuk selamatan sama dengan selamatan yang telah dilaksanakan.
h. Nyewu dina
Selamatan nyewu dina atau nyewu dilaksanakan seribu (Jawa: sewu) hari sejak
kematian seseorang. Selamatan ini dilakukan besar-besaran, sebab dianggap yang
terakhir kalinya. Materi atau perlengkapan sama dengan selamatan terdahulu, tetapi
ditambah dengan memotong kambing, merpati, dan bebek, di samping juga ayam.
Sebelum disembelih, kambing dimandikan dengan air bunga setaman, dikeramasi
dengan air lada atau mangir, diselimuti kafan, dikalungi rangkaian bunga, dan diberi
makan daun sirih. Selain pemotongan hewan-hewan tersebut, juga dilakukan
pelepasan sepasang merpati sesudah kenduri dan pembacaan ayat-ayat Al Quran.
Selain sesajen seperti selamatan terdahulu, masih ditambah sesajen berupa klasa
bangka (tikar), benang lawe, jodhog (tempat menaruh lampu senthir/lampu minyak
tanah), lampu dengan minyak goreng, sisir, minyak wangi, cermin, kapas, kemenyan,
pisang raja, gula kelapa, kelapa utuh, beras, benang jahit, jarum, dan bunga. Pada
selamatan nyewu ini biasanya juga dilaksanakan pemasangan kijing atau nisan,
sehingga upacara selamatan ini juga disebut selamatan ngijing.
Upacara-upacara selamatan tersebut dilakukan kepada setiap orang yang
meninggal, kecuali yang meninggal bayi yang belum umur (trek), artinya belum
saatnya lahir. Dalam keaaan seperti ini, segala bentuk upacara seperti di atas
dilaksanakan sekaligus pada selamatan surtanah. Pemakaman dilakukan di
pekarangan rumah, tidak di makam umum, agar perawatan mudah dan tidak
terlupakan. Bayi trek bila dipelihara dengan baik diyakini sangat membantu orang
tua yang ditinggalkan, misalnya menenteramkan keluarga, membantu mencari
nafkah, dan sebagainya. Bahkan bagi orang tuanya, perlakuan bayi trek disamakan
dengan perlakuan terhadap anak yang masih hidup. Selain kuburannya dirawat
dengan baik, pada malam-malam tertentu dikirim doa dan bunga, kemenyan, sesajen,
dan baju baru! Roh bayi trek dapat dimintai bantuan atau pertolongan oleh orang
tuanya jika sedang menghadapi kesulitan (Mulyadi dkk., 1984: 62).
i. Nyadran
Kegiatan lain dalam hal perawatan kuburan dan penghormatan terhadap roh
orang mati atau roh leluhur adalah selamatan nyadran. Nyadran berarti melaksanakan
upacara sadran atau sadranan yang masih populer di kalangan masyarakat Jawa.
Upacara ini dilaksanakan pada bulan Ruwah (kalender Jawa) atau Sya’ban (kalender
Hijriyah) sesudah tanggal 15 hingga menjelang ibadah puasa Ramadhan (Karkono
Kamajaya P., 1995: 246).
Nyadran dilangsungkan dengan selamatan di rumah dan di makam. Materinya
adalah nasi asahan beserta lauk-pauknya, ditambah apem dan perlengkapannya
berupa tukon pasar. Maksud selamatan ini adalah mengirim doa dan minta berkah
kepada para arwah leluhur. Hal itu tercermin dari doa yang disampaikan pada saat
selamatan yang berbunyi:
Kintun pandonga dhateng leluhur kula saking jaler lan saking estri, ingkang tebih lan ingkang celak, ingkang kerawatan lan ingkang mboten kerawatan. Sedaya wau kula suwun berkah pangestunipun wilujeng.
Kirim doa kepada para leluhur, baik dari lelaki maupun perempuan, yang dekat maupun yang jauh, yang terawat maupun yang tidak terawat. Semua tadi kami minta berkah dan restunya.
Masyarakat percaya pada bulan Ruwah para arwah leluhur mempunyai
kesempatan tilik kubur (berkunjung ke makamnya) dan tilik omah (berkunjung ke
rumah). Karenanya, banyak orang tua melarang anaknya kencing di halaman agar
tidak sampai mengencingi arwah yang sedang tilik omah tersebut.
B. Perspektif Sosiologi Integratif
Islam adalah ajaran normatif yang berasal dari Tuhan. Ia dapat
diakomodasikan ke dalam pelbagai kebudayaan tanpa harus menghilangkan
identitasnya masing-masing. Agama sebagai kepercayaan yang memuat nilai dan
norma kemasyarakatan tidak harus menolak budaya lokal. Islam itu universal,
artinya ia dapat berkembang di mana saja pada masyarakat yang sangat berbeda
kebudayaannya. Di lain pihak, kebudayaan Jawa, menurut Franz Magnis Suseno,
mempunyai ciri khas dalam kemampuannya membiarkan diri dibanjiri oleh
gelombang-gelombang kebudayaan yang datang dari luar, dan dalam benjir tersebut
kebudayaan Jawa mampu mempertahankan keasliannya.
Kebudayaan Jawa justru tidak menemukan diri dan mengembangkan ciri
khasnya dengan isolasi, melainkan dalam pencernaan masukan-masukan kultural
dari kebudayaan lain. Hinduisme dan Bhudisme diterima untuk kemudian dijawakan.
Ketika gelombang Islam masuk ke Jawa, justru kemudian kebudayaan Jawa
menemukan identitas dirinya. Pertemuan Islam bercorak tasawuf dengan kebudayaan
Jawa yang khas tersebut melahirkan corak kebudayaan yang berbeda melalui proses
sinkretisme, seperti upacara selamatan yang berhubungan dengan kematian.
Dari sudut pandang agama, upacara-upacara tersebut tidak dapat dibenarkan.
Alasannya, pertama pembuatan atau penyiapan ubarampe (perlengkapan) selamatan
merupakan cerminan hidup boros yang sangat ditentang Islam, karena Islam
mengajarkan untuk hidup tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Kedua, Islam
mengajarkan bahwa doa tidak perlu perantara (wasilah). Doa adalah komunikasi
langsung antara manusia dengan Tuhan, sehingga memohon berkah dari arwah
leluhur adalah perbuatan menyekutukan Tuhan. Ketiga, mendoakan keluarga, teman,
dan leluhur tidak terbatas sampai dengan saat nyewu saja. Islam mengajarkan
umatnya untuk selalu mendoakan keluarga atau leluhur kapan saja dan di mana saja,
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Keempat, upacara-upacara selamatan yang
dilakukan masyarakat Jawa merupakan tindakan yang tidak rasional. Islam sangat
menghargai akal pikiran yang dipunyai manusia untuk membedakannya dengan
hewan. Islam melarang seseorang bersikap terhadap sesuatu tanpa dasar pengetahuan
(QS. Al Israa’: 36).
Upacara-upacara selamatan bersifat sinkretis animisme-Hindu/Bhuda-Islam
merupakan konsekuensi dari metode penyebaran agama Islam di Jawa yang tidak
gamblang. Selain itu, Sunan Kalijaga dalam upaya penyebaran Islam sangat toleran
pada budaya lokal (www.walisongo_kalijaga.seasite.niu.edu). Ia berpendapat bahwa
masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Mereka harus didekati secara
bertahap, diikuti sambil dipengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan, jika Islam sudah
dipahami dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang.
C. Sosiologi Integratif sebagai Solusi
Tujuan pembelajaran Sosiologi di SMA adalah memberikan dasar-dasar
pengetahuan sosiologi, agar para siswa mampu memahami dan menelaah secara
rasional dan kritis terhadap beberapa konsep dasar, berbagai peristiwa atau fenomena
yang berhubungan dengan kebudayaan (culture). Pemahaman atas fenomena budaya
akan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku siswa dalam lingkungan
budayanya, termasuk pemahaman atas upacara-upacara selamatan yang berhubungan
dengan kematian.
Melalui pembelajaran sosiologi integratif diharapkan siswa mampu
menangkap pesan esensial (essential messages) yang terkandung dalam upacara
tersebut, sehingga ia dapat memposisikan dirinya dan memandang upacara tersebut
merupakan kegiatan kultural, bukan ritual. Sosiologi integratif adalah pembelajaran
sosiologi yang telah diintegrasikan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
melalui pokok bahasan tertentu.
Apabila ditelaah lebih dalam, sebenarnya materi atau perlengkapan upacara
selamatan adalah perlambang atau simbul nilai-nilai yang harus dijalankan manusia.
Sega golong melambangkan kebulatan tekad yang manunggal (Jawa: tekad kang
gumolong dadi sawiji). Dalam hal kematian, baik yang mati maupun keluarga yang
ditinggalkannya sama-sama mempunyai tujuan satu, surga. Sega asahan/ambengan
merupakan lambang pambenganing Pangeran, artinya selalu mendapat ampunan
Tuhan atas segala dosanya dan diterima di sisi-Nya. Tumpeng pungkur
melambangkan perpisahan orang yang mati dan yang masih hidup, karena arwah
orang yang mati akan berada di alam yang lain.
Tumpeng/nasi gunung melambangkan suatu cita-cita atau tujuan mulia seperti
gunung yang besar dan puncaknya tinggi. Selain itu, tempat tinggi adalah tempat
bersemayamnya Tuhan. Ingkung melambangkan sikap pasrah atau menyerah
terhadap kekuasaan Tuhan. Istilah ingkung mempunyai makna dibelenggu (Jawa:
dibanda). Kembang rasulan/kembang telon melambangkan keharuman doa yang
dilontarkan dari hati yang tulus ikhlas lahir dan batin.
Bubur abang-putih melambangkan keberanian dan kesucian. Bubur merah
sebagai tanda bakti kepada roh laki-laki (bapak), sedang bubur putih merupakan
tanda bakti bagi roh perempuan (ibu). Dalam arti yang lebih luas adalah tanda bakti
bagi bapa angkasa ibu pertiwi, atau penguasa langit dan bumi, Tuhan Yang Maha
Esa. Sega punar atau nasi kuning melambangkan kemuliaan atau jamuan mulia bagi
yang dipujinya. Apem melambangkan payung dan tameng, maksudnya agar roh
mendapat perlindungan dari Tuhan.
Ketan mempunyai sifat lekat (Jawa: pliket/keraket), sehingga dimaksudkan
sebagai lambang agar antara roh orang yang meninggal dengan yang ditinggalkan
selalu raket atau erat. Kambing, merpati dan itik melambangkan kendaraan yang
akan dinaiki oleh roh orang yang meninggal setelah hari ke-1000. Jika dalam
perjalanannya melalui daratan, kambing dijadikan sebagai kendaraan. Lewat laut
naik itik, dan jika perjalannya melalui angkasa akan mengendarai merpati.
Materi sajian lain seperti klasa, benang lawe, jodhog, senthir, clupak, lenga
klentik, jungkat (sisir), minyak wangi, cermin, kapas, pisang, beras, gula, kelapa,
dan jarum merupakan lambang segala perlengkapan sehari-hari untuk bekal di alam
baka.
a. Model Integrasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum 2006,
memberikan keleluasaan kepada guru untuk menjabarkan dan menyesuaikannya
dengan kondisi masing-masing sekolah. Dalam proses pembelajaran, guru sosiologi
dapat menentukan sendiri metode yang diterapkan, penilaian, dan sumber belajar
yang akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses
pembelajaran siswa, guru harus memperhatikan tujuan, sifat pokok bahasan, sumber
belajar yang tersedia, dan waktu yang tersedia.
Pembelajaran tentang multikulturalisme diintegrasikan pada
Kompetensi Dasar (KD) Proses Perubahan Sosial di Masyarakat pada kelas XII IPS,
agar para siswa memahami budayanya sendiri dan tidak terjerumus pada taqlid buta.
Mengingat keterbatasan waktu yang disediakan, maka cara pengintegrasian adalah
dengan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pelaksanaan
upacara selamatan yang berhubungan dengan kematian pada desanya masing-masing
berdasarkan kelompok yang mereka tentukan. Informasi dapat diperoleh dari modin
(kaum), juru kunci, atau tokoh masyarakat di desanya masing-masing. Laporan hasil
penelitian masing-masing kelompok selanjutnya dipresentasikan di depan kelas
untuk didiskusikan.
Untuk mengetahui dampak proses pembelajaran, dilakukan pre test dan post
test kepada seluruh siswa. Pergeseran hasil antara pre test dan post test itulah yang
digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.
b. Hasil Penelitian
Penelitian dilakukan terhadap 114 siswa kelas XII IPS SMAN 1 Jatinom
Klaten tahun pelajaran 2009/2010, yang terbagi dalam tiga kelas, yaitu XII IPS 1,
XII IPS 2, dan kelas XII IPS 3, dengan jumlah masing-masing kelas adalah 38 siswa.
Setiap kelas terdiri dari 4 kelompok dengan tugas mengamati perubahan sosial yang
terjadi di kampung masing-masing, terutama dalam pelaksanaan upacara tradisional
yang berhubungan dengan kematian seseorang. Laporan penelitian mereka kemudian
didiskusikan di kelas masing-masing pada jam pelajaran Sosiologi.
Sebelum melaksanakan penelitian di lapangan, para siswa mengisi
angket (pre-test) yang dibuat guru untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, dan
keterlibatan mereka dalam upacara tradisional. Berdasarkan pre-test yg dilakukan,
diketahui bahwa hampir semua siswa (97,37%) mengetahui adanya upacara
kematian di lingkungan sekitarnya. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagian besar
siswa bertempat tinggal di pedesaan yang masih lekat dengan upacara-upacara
tradisional dalam kehidupan sehari-harinya.
Meskipun hampir semua siswa mengetahui adanya upacara tradisional,
tidak semua siswa ikut terlibat dalam kegiatan upacara tersebut. Hanya 62,28% siswa
yang menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan tersebut sebelumnya, sedangkan
37,72% menyatakan belum pernah atau tidak mau terlibat dalam kegiatan tersebut.
Siswa yang menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan tersebut sebagian besar
(61,97%) melakukan kegiatan dengan alasan melaksanakan tradisi (adat-istiadat),
22,54% dengan alasan melaksanakan perintah orang tua, 8,45% karena
melaksanakan perintah pengurus desa, dan 7,05% melaksanakan tanpa mempunyai
alasan tertentu.
Siswa yang menyatakan tidak pernah atau tidak mau terlibat dalam
kegiatan upacara tradisional didorong oleh alasan utama agama. Sebanyak 90,70%
siswa tidak terlibat dalam upacara tradisional dengan alasan kegiatan tersebut
dilarang agama Islam (musyrik). Hanya 4,65% yang menyatakan tidak terlibat
karena di kampung tempat tinggalnya masyarakat tidak lagi melaksanakan, 2,33%
karena dianggap tindakan pemborosan, dan 2,33% lainnya merasa kegiatan upacara
tradisional tersebut tidak penting untuk dilaksanakan.
Terdapat gejala yang menarik dalam penelitian ini, yaitu tidak sampainya
pesan esensial yang terkandung dalam upacara tradisional tersebut. Tabel berikut
dapat digunakan untuk memperjelas fenomena tersebut:
Tabel 1. Jumlah Siswa Berdasarkan Pengetahuannya Terhadap Makna Simbul dalam Upacara Tradisional
KeterlibatanTahu Makna Tidak tahu Makna
f % f %Ikut 0 0.00 71 62.28
Tidak Ikut 2 1.75 41 35.96
Jumlah 2 1.75 112 98.25Sumber: Data Primer
Berdasarkan data tersebut diketahui, bahwa para siswa yang ikut terlibat
dalam kegiatan, tidak mengetahui makna simbul-simbul yang ada pada kegiatan
tersebut. Hanya 2 siswa yang menyatakan tahu makna simbul yang ada dan
menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan upacara tradisional. Kondisi
tersebut tentu saja tidak menguntungkan, karena para siswa melaksanakan sebuah
kegiatan tanpa mengetahui makna atau tujuan yang mereka lakukan.
Penelitian lapangan oleh para siswa dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2009
sesuai dengan Rencana Program Pengajaran (RPP) yang ada. Pada saat itu
masyarakat Jawa tengah melaksanakan salah satu upacara tradisional Nyadran,
sehingga mempermudah kegiatan siswa. Kegiatan penelitian lapangan dianjutkan
dengan penyusunan dan diskusi temuan di lapangan oleh masing-masing kelompok.
Kegiatan penelitian di lapangan dan diskusi laporan di dalam kelas berhasil
memperkaya wawasan siswa tentang kegiatan upacara tradisional yang berhubungan
dengan kematian. Data pada tabel berikut memperlihatkan pemahaman para siswa
terhadap simbul-simbul perlengkapan pada upacara tradisional:
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Siswa Atas Pemahaman Makna Simbul-simbul Perlengkapan Upacara Tradisional
KeterlibatanTahu Makna Tidak Tahu Makna
f % f %Pre-test 2 1.75 112 98.25Post-test 114 100.00 0 0.00Perubahan 112 98.25 -112 -98.25
Sumber: Data Primer
Penelitian di lapangan dan diskusi di dalam kelas ternyata mampu menambah
wawasan para siswa terhadap pelaksanaan upacara tradisional. Pada saat pre-test
berlangsung hampir semua (98,25%) siswa tidak mengetahui makna yang
terkandung dalam perlengkapan upacara. Keadaan tersebut berubah total saat post
test berlangsung. Semua (100%) siswa mengetahui makna simbul-simbul
perlengkapan yang dipakai dalam upacara tersebut.
Gambar 1. Diskusi laporan hasil penelitian
Pemahaman makna atau pesan yang terkandung dalam perlengkapan upacara
tradisional tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan sikap para siswa terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh perbandingan jumlah siswa
yang menyatakan boleh melaksanakan kegiatan tersebut pada saat pre test dan
setelah post-test. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Siswa Yang Menyatakan Boleh-Tidak Melaksanakan Upacara Tradisional
WaktuBoleh Dilaksanakan Tidak Boleh Jumlah
f % f % f %Pretest 73 64.04 41 35.96 114 100.00Post-test 111 97.37 3 2.63 114 100.00
Sumber: Data Primer
Data tersebut menunjukkan bahwa setelah melakukan kegiatan penelitian
lapangan dan diskusi laporan penelitian, para siswa mampu melihat fenomena
upacara tradisional yang berhubungan dengan kematian sebagai sebuah kegiatan
kultural, bukan kegiatan ritual, sehingga 97,37% siswa menyatakan bahwa
pelaksanaan upacara tradisional merupakan sebuah kegiatan yang sah untuk
dilaksanakan.
D. Penutup
Di antara ratusan suku bangsa di Indonesia, suku bangsa Jawa jumlah
populasinya paling banyak dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam. Akan
tetapi Islam yang berkembang di Jawa mempunyai karakteristik yang khas, karena
pertemuannya dengan kebudayaan yang telah ada sebelum datangnya Islam. Islam
yang bercorak tasawuf mendapat tempat yang baik untuk tumbuh ketika bertemu
dengan budaya Jawa dan terjadilah proses sinkretisme. Sinkretisme tersebut
melahirkan bentuk-bentuk upacara yang berhubungan dengan kematian seperti
upacara surtanah, nelung ndina, mitung ndina, matang puluh, nyatus, mendhak pisan,
mendhak pindho, nyewu, dan nyadran.
Essential message yang dibawa upacara-upacara tersebut sebenarnya baik,
jika dimengerti hakikatnya. Namun, para siswa ternyata hampir tidak ada lagi yang
mengetahui hakikat pelaksanaan upacara-upacara tersebut yang dikemas dalam
lambang-lambang sesaji. Untuk itu, pembelajaran sosiologi integratif dalam Standar
Kompetensi Memahami Dampak Perubahan Sosial menjadi suatu keharusan.
Sifat kebudayaan Jawa yang khas dan metode pengislaman Walisanga yang
tidak gamblang menyebabkan beberapa tradisi di Jawa mempunyai potensi untuk
menyimpang. Untuk itu guru harus berusaha mengelola proses pembelajaran dengan
menyesuaikan waktu yang tersedia agar para siswa mampu menemukan essential
message dari upacara-upacara atau tradisi yang berkembang di dalam masyarakat
Jawa melalui wawancara dengan nara sumber, buku, CD, atau sumber lainnya.
_____________________
PUSTAKA ACUAN
H.J. de Graaf dan TH. G. TH. Pigeaud. 1986. Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa Kajian Sejarah Politik Abad ke 15 dan ke-16. Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers dan KITLV.
http://www.petra.ac.id/english/eastjava/culture/ident.htm
http://www.walisongo_kalijaga.seasite.niu.edu/Indonesian/Islam/Kalijaga.htm
http://202.159.18.43/jsi/131sugianto.htm
James Danandjaja. 1991. Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Karkono Kamajaya Partokusumo. 1995. Kebudayaan Jawa, Perpaduannya dengan Islam. Yogyakarta: IKAPI Cabang Yogyakarta.
Koentjaraningrat (ed). 1999. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Mulyadi dkk. 1984. Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi DIY. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1982-1983.
Siti Waridah Q. dkk. 2000. Sosiologi untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Bumi Aksara.
Zulyani Hidayah. 1999. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: LP3ES.