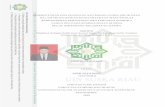Manusia citra fotografis dan pembentukan opini dalam nilai kebudayaan visual
-
Upload
pustral-ugm -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Manusia citra fotografis dan pembentukan opini dalam nilai kebudayaan visual
Manusia , citra fotografis dan pembentukan opini dalam nilai
kebudayaan visual
Kebudayaan merupakan rangkaian dari aktivitas yang
berulang-ulang sehingga pada akhrinya membentuk kebiasaan yang
membentuk pola dalam masyarakat, pola dalam masyarakat itu
meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan
adat istiadat. Selo Soemarjan dan Soleiman Soemardi1
mendefinisikan kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan
cipta masyarakat. Dari kegiatan yang berpola inilah, kemudian
menghasilkan wujud-wujud dalam kebudayaan. Wujud dari
kebudayaan ini merupakan hasil karya, rasa dan cipta dari
masyarakat yang berupa benda-benda atau pola-pola perilaku.
J.J. Hoenigman2 membedakan wujud kebudayaan menjadi tiga,
yaitu gagasan, aktivitas dan artefak. Gagasan (wujud ideal)
adalah kebudayaan sifatnya abstrak berupa ide-ide, gagasan,
nilai-nilai, norma-norma dan peraturan; tidak dapat diraba,
atau disentuh. Aktivitas adalah wujud kebudayaan yang sering
disebut dengan sistem sosial, sifatnya konkret karena dapat
diamati dan didokumentasikan. Artefak adalah wujud kebudayaan
fisik yang berupa hasil dari gagasan dan aktivitas manusia
dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat
dan didokumentasikan.
Menurut Koentjaraningrat (1994:14-15), Suatu sistem
kelakuan khas dari kelakuan berpola (wujud dari kebudayaan
yang berupa aktivitas/kelakuan) beserta komponen-komponennya,
ialah: sistem norma (wujud ideal dari kebudayaan) dan
peralatannya (wujud fisik dari kebudayaan) ditambah dengan
manusia atau personel yang melaksanakannya kelakuan berpola,1 http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya2 ibid.
merupakan suatu pranata atau institution. Pranata atau
institution inilah membuat kelakuan berpola dari manusia dalam
kebudayaannya.
Bagan 1.1. Bagan komponen-komponen dari pranata Sosial
Bagan diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan
bermasyarakat, semua wujud-wujud kebudayaan tidak bisa
terpisahkan dan saling berkaitan. wujud kebudayaan yang berupa
aktivitas/kelakuan mengaitkan semua wujud kebudayaan dengan
manusia yang kemudian membentuk sistem nilai yang membuat
suatu kelakuan yang berpola dalam masyarakat.
Keterkaitan komponen-komponen tersebut dalam kebudayaan
modern sekarang sangat terkait dengan pembentukan budaya
visual dalam kehidupan manusia modern. Karena budaya visual
merupakan salah satu wujud kebudayaan yang berupa konsep
(nilai) dan materi (artefak/benda) yang ditangkap oleh panca
indera visual manusia kemudian dapat dipahami sebagai tautan
pikiran untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Wujud dari
kebudayaan visual yang berupa artefak inilah yang
diapresiasikan manusia kemudian membentuk sebuah aktivitas
komunikasi non-verbal yang akhirnya memunculkan pemaknaan-
pemaknaan terhadap artefak tersebut. Dalam studi ilmu
komunikasi (Mulyana, 2003:380), artefak adalah benda apa saja
yang dihasilkan kecerdasan manusia. Benda-benda yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dalam interaksi
manusia, sering mengandung makna-makna tertentu.
Dengan demikian, budaya visual meliputi berbagai aspek
dalam wujud kebudayaan yang berupa gagasan yang kemudian
menciptakan wujud akhir yang berupa karya atau benda, Karya
atau benda-benda sebagai wujud akhir budaya visual meliputi
berbagai bentuk media komunikasi visual seperti foto, film,
iklan, siaran televisi, media cetak hingga mode pakaian; karya
desain dan karya senirupa. Benda-benda dalam kebudayaan visual
tersebut memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri, sehingga
kebudayaan visual menjadi sangat dinamis. Karena budaya visual
merupakan budaya yang bermuatan nilai, serta amat terpengaruh
oleh situasi sosial yang terjadi di zamannya.
Media komunikasi visual yang berupa foto dapat dipandang
sebagai budaya visual yang sangat fungsional serta telah
menjadi bagian kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di dalam
kehidupan masyarakat modern foto merupakan hasil kebudayaan
yang menyentuh sisi kehidupan manusia tentang arti dan makna
dalam sebuah kehidupan. Foto merupakan wujud dari pencapaian
kreatifitas serta kecerdasan manusia yang dapat segera diserap
secara visual oleh panca indera manusia. Oleh karena itu foto
merupakan fenomena visual yang mengalami perkembangan
teknologi cukup pesat.
Kehadiran fotografi disebut sebagai alat perekam dan
penghadir ulang sebuah kenyataan yang ampuh. Fotografi
disebut-sebut mempunyai kepekaan dalam merekam detail membuat
manusia modern mengagungkannya sebagai kemajuan manusia dalam
merekam kenyataan yang ada, baik dari sejarah sampai dengan
foto-foto yang sifatnya dokumentasi sampai dengan foto-foto
yang bersifat komersial. Serbuan budaya populer membuat
fotografi menggiring pada anggapan sebagai media penghadir
kenyataan yang objektif. Dengan perkembangan masyarakat modern
yang membutuhkah kecepatan dan ketepatan informasi membuat
fotografi menjadi salah satu media yang paling handal.
“What is true of the pen is equally true of the camera.”(Don Slater,
1999:289). Sebuah foto biasanya menggambarkan sebuah realitas
yang sebenarnya kedalam bentuk gambar. Dan karena fungsi
itulah, banyak masyarakat menggunakan foto kedalam berbagai
aktivitas mereka sehari-hari. Sebagian besar masyarakat saat
ini telah mengenal kamera dan foto dan menjadikannya sebagai
satu kegiatan dalah kehidupan mereka masing-masing. Banyak
masyarakat memanfaatkan fungsi kamera dan foto untuk
mengabadikan atau merekam berbagai kegiatan dan momen-momen
penting mereka, mulai dari kelahiran, wisata, kegiatan
rutinitas, ataupun saat menghabiskan waktu dengan keluarga.
Sehingga dapat dikatakan bahwa foto telah masuk kedalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Fotografi sudah menjadi bagian yang sangat penting bagi
masyarakat. Penelitian yang diadakan di Inggris tentang jumlah
orang yang mempunyai kamera bisa menjadi representasi bagi
masyarakat di dunia. Ini menunjukan bagaimana kebudayaan
visual dalam bidang fotografi membuat pola dalam perilaku
masyarakat. Walaupun sebenarnya mereka hanya menggunakan
fotografi sebagai keperluan dokumentasi, tetapi penelitian ini
menunjukan bahwa foto dan fotografi sangat dekan dengan
kehidupan masyarakat.
Ada anggapan bahwa kepercayaan pada budaya visual yang
berasal dari budaya lensa ini lahir pada abad ke-19 ketika
kamera ditemukan. Saat Revolusi Industri dengan teknologinya
tengah marak, tatanan masyarakat kapitalisme di Barat tentu
mulai mengenal dan terpengaruh budaya baru ini. Tetapi
anggapan tadi sesungguhnya terlalu sederhana. Sebab jauh
sebelumnya, di tahun 1285, telah ditemukan kaca pembesar
sederhana yang mengawali wawasan baru pada pandangan ilmuwan.3
Sekitar tahun 1550, Girolamo Cardano tercatat sebagai orang
pertama yang memasang lensa yang memungkinkan adanya bukaan
(aperture) pada camera obscura (kamera lubang jarum). Lensa dari
kaca--berbentuk bikonveks seperti butir buah lentil (miju-
miju), sebuah kata yang menyebabkan kita menyebutnya lensa--
yang dipasang pada kotak kedap cahaya (kamera lubang jarum)
telah menjadi alat bantu sangat penting bagi para pelukis di
zaman itu.4
Penggunaan fotografi dan media visual lainnya banyak
digunakan untuk propaganda politik oleh berbagai pihak yang
berebut pengaruh. Berbagai macam bentuk propaganda visual
digunakan dalam kampanye pro demokrasi dan sosialis kiri
melawan fasisme dan Nazi di Eropa. Propaganda visual itu
dikemas dalam berbagai macam, baik secara artistik dengan
menggunakan montase seperti John Heartfield atau Hanna Hoch
maupun jurnalistik-dokumenter seperti Robert Capa, Cartier-
Bresson, Centelless, dan teman-temannya. Mereka membuat karya-
karya foto yang membawa berbagai macam akibat, baik karena
citra yang dirancang dengan penuh kesadaran maupun hal-hal
yang terjadi di luar kehendak mereka.
3
4 jurnalkalam.org/index-php/articles/view/57
Dihadirkannya kembali kenyataan dalam bentuk visual
berperan besar pada pembentukan opini publik. Para fotografer
jurnalistik maupun fotografer seni dalam dunia sosialis sangat
meyakini bahwa fotografi dapat berperan dan bertanggung jawab
dalam pembentukan masyarakat yang ideal, berlawanan dengan
mereka yang mengagungkan obyektivitas dalam fotografi, yang
akhirnya menggunakan fotografi untuk memanipulatif. David
Ogilvy--tuhan di dunia periklanan--sejak awal 1940-an
menyatakan bahwa untuk mempengaruhi masyarakat, lebih baik
menggunakan foto daripada seribu sketsa gambar tangan.
Meskipun itu kiri atau kanan, ideal atau komersial, dapat
disadari foto memiliki daya pengaruh yang begitu besar untuk
membentuk opini masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri
bahwa siapapun yang menghadirkan kembali kenyataan melalui
foto sebenarnya tengah mempengaruhi pandangan tentang
pemirsanya.
Menurut Susan Sontag (1999:87): “Photography, which has so many
narcissitic uses, is also a powerful instrument for depersonalizing our relation to the
world; and the two uses are complementary….In the real world, something is
happening and no one knows what is going to happen. In the image-world, it has
happened, and it will forever happen in that way.” Fotografi selain
mempunyai kegunaan dalam kegiatan narsisme diri, fotografi
juga mampu menjadi sebuah alat yang mengurangi karakter
hubungan kita dengan lingkungan sosial, dan kedua peranan
fotografi tersebut merupakan sesuatu yang saling melengkapi
satu sama lain. Karena saat kita masuk kedalam dunia
fotografi, hidup kita akan semakin terpisahkan dengan realitas
yang sedang terjadi karena kita hanya melihat pada realitas
yang terbentuk didalam sebuah gambar foto dan makna yang
terdapat pada realitas dalam foto dan dunia nyata dapat
dikatakan berbeda. Dalam dunia nyata, saat sebuah fenomena
sedang berjalan, tak seorangpun tahu akan apa yang terjadi
kedepannya atas fenomena tersebut. Sedangkan pada dunia gambar
foto, realitas yang terdapat didalamnya merupakan sebuah
realitas yang telah terjadi sebelumnya dan akan selalu terjadi
seperti yang terdapat pada gambar tersebut.
Sebuah kisah menarik ketika Roland Barthes membawa
skandal fotografis dalam peristiwa Komune Paris. Berawal dari
sebuah foto yang menampilkan sosok-sosok yang berjajar dengan
pose bangga di depan kamera. Kemenangan baru saja mereka raih.
Mereka berhasil menguasai salah satu sudut Paris, merebutnya
dari tangan kaum borjuis konservatif. Teori telah
dipraktekkan, dan mereka melihat masa depan realisasi sebuah
ideologi. Dalam pose itu, setiap pribadi begitu mengemuka,
penuh dengan cita-cita. Setiap wajah mengguratkan kehendak dan
keberanian dalam kekhasan ekspresi masing-masing. Tanpa mereka
sangka, justru karena foto inilah hidup mereka berakhir.
Ketika sebuah foto lain berhasil membangkitkan amarah warga
Paris pada para anggota Komune Paris itu. Foto yang
menampilkan mayat polisi bergelimpangan, dengan keterangan
mereka dibantai para pejuang revolusioner itu. Foto itu
membuat warga Paris berubah pikiran dan memberi mandat kepada
polisi untuk menghukum kaum revolusioner itu sesuai dengan
perbuatan mereka. Dari foto kemenangan itu, masing-masing
orang itu dikenali, kemudian satu demi satu ditembak mati,
hampir semuanya. Namun, warga Paris tidak tahu bahwa mayat-
mayat yang bergelimpangan yang mereka lihat itu, bangkit
kembali setelah sesi pemotretan selesai.5
Skandal fotografis Roland Barthes di Paris menunjukan
fotografi dalam sebuah kebudayaan menunjukan nilai tersendiri
yaitu free value. Free value merupakan sebuah nilai bebas atau
5 http://jurnalkalam.org/edisi/2007/fotografi_pengantar.html
mempunyai banyak arti. Nilai ini terlihat ketika pada saat
foto bisa menunjukan arti dan makna yang berbeda bagi setiap
orang yang melihatnya. Bagi kaum revolusioner Paris, foto yang
diambil Rolan Barthes merupakan foto kejayaan dan kemenangan.
Di lain pihak bagi kaum borjuis koservatif di Paris, foto yang
diambil Barthes merupakan foto yang membuat mereka malu dan
mereka melihat tokoh-tokoh di balik pemberontakan dari foto
itu. Kebebasan dalam memaknai foto inilah akhirnya bisa
menjadi kelemahan sebuah foto saat orang tidak tahu bagaimana
cara memaknainya dan jatuh ke tangan orang yang bertentangan
opini. Baik atau buruknya makna yang dibawa oleh foto
tergantung dengan kepentingan yang digunakan seseorang saat
mempublikasikan foto tersebut.
Di Indonesia keberadaan budaya visual sangat bisa
dirasakan. Mulainya periode pemilu di tahun 2009 membuat
banyak politisi dan partai-partai menggunakan media komunikasi
visual untuk mempengaruhi masyrakat agar saat pemilihan nanti
masyarakat memilih mereka. Media-media visual yang banyak
dilatar belakangi foto-foto tokoh atau aktivitas-aktivitas
yang pernah mereka lakukan membentuk opini tersendiri di
masyarakat tentang pandangan calon pemimpinnya. Kesadaran akan
sebuah kebudayaan visual di Indonesia membuat para pelaku
marketing politik berlomba-lomba mencitrakan tokoh politik
atau partai politik melalui visualisasi menggunakan media
massa. budaya visual yang ada di Indonesia sebenarnya sudah
ada sejak masa lalu, di mana siswa-siswi di sekolah
diperlihatkan foto-foto bung Karno dan bung Tomo pada masa
perebutan kemerdekaan. Dengan adanya foto-foto tersebut
akhirnya masyarakat dapat menyadari betapa berwibawanya para
pemimpin-pemimpin kita pada masa perebutan kemerdekaan.
Berkembangnya teknologi membuat media-media komunikasi
yang ada dalam budaya visual menjadi berkembang dan sangat
beragam. Di mulai dari media yang hanya mempunyai sisi visual
saja seperti foto, sampai dengan media yang mempunyai sisi
audio dan visual yang biasa disebut dengan film. Perbandingan
kedua kekuatan media ini sangatlah menarik, karena foto hanya
mempunyai kekuatan visual saja dibandingkan dengan film. Jika
dibandingkan secara linear kekuatan foto memang kalah
dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh film. Film
dengan kekuatan audio visualnya lebih mudah mempengaruhi
masyarakat. Kekuatan audio visualnya bisa membentuk atmosfer
tersendiri di benak masyarakat dan makna yang disampaikannya
menjadi lebih jelas, karena ada kekuatan audio dan visual.
Kekuatan yang dimiliki oleh film memang menjadikan film
lebih unggul dalam membentuk retorika di masyarakat. Akan
tetapi, untuk memproduksi sebuah film haruslah dengan biaya
yang sangat mahal dibanding memproduksi sebuah foto. Sifat-
sifat yang dimiliki oleh film tidak se-fleksibel foto ketika
ingin mempublikasikannya. Film tidak memiliki sifat spaceless,
karena untuk mempublikasikannya dibutuhkan peralatan khusus
yang bisa menayangkannya. Walaupun sudah memasuki era
multimedia, foto masih mempunyai ruang tersendiri dalam
kebudayaan visual. Di mana foto dan film mempunyai dan
bergerak di ruang masing-masing untuk mempengaruhi masyarakat.
Kekuatan foto dalam kebudayaan visual dapat dibuktikan
dengan banyaknya konsumsi masyarakat terhadap kamera foto.
Dalam melihat hasil foto tidak dibutuhkan sebuah peralatan
khusus, seperti saat masyarakat ingin melihat hasil yang
diproduksi dari kamera video. Foto bisa dilihat setiap saat
dan di mana saja. Ini yang menjadikan media komunikasi yang
disebut dengan foto ini mempunyai sifat timeless. Foto merupakan
media komunikasi yang tidak akan lekang oleh waktu, karena
tidak membutuhkan perawatan yang khusus untuk menyimpan
dokumen-dokumen yang berbentuk foto. Sifat foto yang sangat
fleksible membuat media ini banyak digunakan untuk
kepentingan-kepentingan tertentu di media massa.
Pada abad ke-19 para ilmuwan mengira bahwa apa yang
ditangkap pancaindra kita sebagai sesuatu yang nyata dan
akurat. Para psikolog menyebut mata sebagai kamera dan retina
sebagai film yang merekam pola-pola cahaya yang jatuh di
atasnya. Para ilmuan modern menantang asusmsi itu: kebanyakan
percaya bahwa apa yang kita amati dipengaruhi sebagian oleh
citra retina mata dan terutama kondisi pikiran pengamat
(zannes, 1982:27). Oleh karena itu gambar-gambar dalam media
visual tersebut mengkonstruksi pikiran manusia melalui suatu
proses aktif dan kreatif yang biasa disebut presepsi. Presepsi
adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih,
mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan
kita, dan proses tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku kita
(Baron, Paulus, 1991:34). Pada akhirnya kebudayaan visual
melalui pencitraan fotografis mempunyai pengaruh yang sangat
kuat dalam kehidupan kebuadayaan visual manusia.
Reference
Taylor, Lucien., et al. Visualizing Theory. New York and London.
Routledge. 1994.
Evans, Jessica and Stuart Hall., et al. Visual Culture: The Reader.
London. SAGE Publications. 2004.
Berger, Arthur A. Seeing is Believing: an Introduction to Visual
Communication. San Fransisco. San Fransisco State University.
2008.
Mlauzi, Linje M., “Reading Modern Ethnographic Photography: Semiotic
Analysis of Kalahari Buhsmen Photograph by Paul Weinberg and Sian Dunn”.
Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama. 1994.
http://jurnalkalam.org/index-php/articles/view/57 (diakses
tanggal 12 Maret 2009)
http://jurnalkalam.org/edisi/2007/fotografi_pengantar.html
(diakses tanggal 12 Maret 2009)
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya (diakses tanggal 12 Maret
2009)
http://www.dikti.org/files/active/0/TENTANG%20BUDAYA
%20VISUAL.doc (diakses tanggal 12 Maret 2009)
http://en.wikipedia.org/wiki/Photography (diakses tanggal 12
Maret 2009.