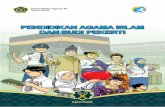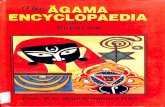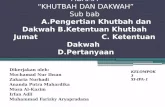M Ridho PLURALISME AGAMA NEGARA AGAMA SIPIL
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of M Ridho PLURALISME AGAMA NEGARA AGAMA SIPIL
PLURALISME AGAMA, NEGARA DAN AGAMA SIPIL
Ditulis untuk tugas Mata Kuliah Filsafat Ilmu
Dosen Pengampu: Adian Husaini, Ph.D
Oleh,
Program Studi Magister Ekonomi
Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA)
PLURALISME AGAMA, NEGARA DAN AGAMA SIPIL
Ditulis untuk tugas Mata Kuliah Filsafat Ilmu
Dosen Pengampu: Adian Husaini, Ph.D
Oleh, Muchamad Ridho Hidayat
Program Studi Magister Ekonomi Islam (Konsentrasi Zakat)
Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA)
Bogor
PLURALISME AGAMA, NEGARA DAN AGAMA SIPIL
Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA)
I. Pendahuluan
Gagasan pluralisme berasal dari peradaban Barat-Kristen. Kelahirannya memiliki kaitan erat
dengan sekularisme dan liberalime yang menjamur setelah berakhirnya era hegemoni gereja.
Menurut Adian Husaini, peradaban Barat menjadi sekular-liberal karena tiga hal, yaitu problem
sejarah Kristen, problem teks Bible, dan probel teologi Kristen1. Dalam kaitannya dengan agama,
problem ini meniscayakan tercampurnya agama (dalam hal ini Kitab Suci) dengan berbagai
ajaran buatan manusia. Hal itu dikarena agama –yang seharusnya menjadi solusi komprehensif –
membutuhkan tambahan elemen lain.
Hendrik Kraemer, seperti dikutip Djohan Efendi dalam pengantar Agama - Agama Manusia
(hlm. ix) menyatakan bahwa semua agama, entah disadari atau tidak oleh para penganutnya
sudah memasuki suatu priode krisis yang berlangsung terus dan mendasar. Dr. Malachi Martin,
seorang pastor Yesuit dan guru besar pada Pontifical Biblical Institute, Roma, menyimpulkan hal
yang sama. Dalam bukunya yang berjudul The Encounter ada topik Religions in Crisis Martin
menulis:
Apapun yang sekarang ini dilakukan oleh semua agama jelas tidak menjadi persoalan. Tak satu pun dari ketiga agama yang telah kita bicarakan (Yahudi, Kristen dan Islam, red) mampu mengendalikan perkembangan umat manusia dewasa ini. Manusia akan kehilangan harapan apabila kecenderungan satu-satunya digerogoti pada akarnya. Dalam keadaan ini, “Tuhan” benar-benar mati. Akhir dominasi agama-agama tersebut mulai mengila-ulangi cerita mengenai kepercayaan individu tentang semua hal yang tidak esensial, tentang semua hal yang diraih oleh peristiwa sejarah dan oleh regionalisme dalam berbagai bentuk. Gambaran di atas bsia diuji hanya pada masa belakangan ketika agama tersebut diguncangkan oleh kesulitan-kesulitan internal dan keterbatasan-keterbatasan eksternal. Kecuali beberapa perkembangan yang dialamai sukar untuk menyaksikan bagaimana ketiga agama itu melepaskan diri dari kemunduran total2.
Martin beranggapan bahwa periode keberhasilan agama-agama tersebut sudah berakhir. Semua
berada dalam keadaan krisis karena sudah tidak mampu memberi jawaban bagi manusia modern
terhadap persoalan-persoalan etis mereka. Agama-agama itu tidak mampu mempersatukan umat
manusia. Rumusan-rumusan ajaran dan pemecahan atas berbagai masalah yang dihadapi umat
manusia tidak digubris lagi. Prof. Rasjidi menjawab pertanyaan “Apakah agama masih
diperlukan?” dengan jawaban, agama masih diperlukan. Beliau menjelaskan bahwa manusia
1 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: 29 2 Seperti dikutip Djohan Efendi dalam pengantar Agama-Agama Manusia ix-x
yang mencapai kemajuan merasa lebih membutuhkan agama. Tanpa agama kemajuan kehidupan
manusia tidak akan memberikan kebahagiaan3.
Pada saat krisis seperti ini, pembicaraan tentang kebangkitan kembali agama-agama menjadi
penting. Lebih-lebih ketika ada anggapan bahwa ideologi-ideologi sekular menjanjikan
perbaikan nasib manusia. Toynbee pernah mengatakan, “Persoalan masa depan agama timbul
karena semua agama yang ada sekarang terbukti tidak lagi memuaskan. Agama di masa depan,
tidak mesti merupakan agama yang sama sekali baru”. Ia juga mengatakan bawah agama
tersebut, “bisa merupakan versi baru agama lama.” Namun bila agama lama harus dihidupkan
dalam bentuk yang mampu menjawab kebutuhan baru umat manusia, “bisa jadi agama itu
ditransformasikan begitu radikal hingga nyaris tak dikenal lagi.”4 Dari sinilah ide ‘campur-sari’
agama-agama atau pluralisme agama lahir dan berkembang. Agama-agama baru akan dibuat,
sedangkan agama-agama lama akan lahir dalam versi yang baru.
Meskipun asal-usul paham ini berasal dari Barat, akan tetapi paham ini sudah berkembang
dengan sedemikian rupa hingga memiliki berbagai variasi bentuk dan model. Anis Malik Thoha
dalam disertasinya menyebutkan empat tren utama dalam pluralisme agama. Pertama, tren
humanisme sekular yang dibangun di atas konsep sentralisasi manusia dan sekularisasi.
Representatif tren ini kebanyakan dari kalangan politikus. Kedua, tren teologi global (global
theology), yang mengacu kepada rekonsepsi agama Wifred C. Smith dab teori ‘The Real’ John
Hick. Ketiga, tren sinkretisme (syncretic) dengan pondasi utama gagasan terbaginya kebenaran
dalam agama-agama dan oleh karena itu agama-agama tersebut saling melengkapi. Keempat,
tren hikmah abadi (perennial philosopy) yang berupaya membedakan antara hakikat transenden
dan hakikat keagamaan5.
Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, tren Teologi Global dan Kesatuan Transenden Agama-agama
(tren hikmah abadi, red) lahir dari motif yang berkebalikan, sehingga membangun gagasan dan
prinsip yang saling menyalahkan6. Aliran yang pertama pada umumnya diwarnai kajian
sosiologis, sedangkan aliran yang kedua diwarnai kajian filosofis dan teologis7. Berbeda dengan
3 Prof. H.M. Rasjidi, Empat Kuliah Agama Islam , hlm.17. 4 Lihat, Djohan Efendi dalam pengantar Agama-Agama Manusia xi 5 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, hlm. 7-8 6 Majalah Islamia Thn.I, No.3, hlm.6 7 Ibid, hlm.6-7
dua tren tersebut, humanisme sekular lebih diwarnai oleh kajian politik. Tren ini lahir karena
krisis politik yang pada akhirnya mengakibatkan apa yang disebut sebagai krisis agama.
Makalah ini akan membahas seputar pluralisme agama dan kaitannya dengan politik (dan secara
khusus negara-bangsa). Untuk memahami lebih dalam tentang hal tersebut, akan dipaparkan
tentang konsep agama dan keterkaitannya dengan politik dan negara.
II. Konsepsi Agama
Agama merupakan tema yang menarik untuk dibicarakan. Sebab ia memiliki peran penting
dalam kehidupan manusia. Tidak hanya para pengikut para Nabi, kaum athies pun rajin
mendiskusikan tema ini. Sebagaimana yang sudah dikenal dalam kajian sosiologi, agama adalah
bagian dari kebudayaan. Paling tidak hal ini diterima oleh siswa humaniora dan para budayawan.
Apa definisi agama? Seperti apakah konsepnya? Menurut KBBI, agama adalah ajaran, sistem yg
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kpd Tuhan Yang Mahakuasa serta tata
kaidah yg berhubungan dng pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya8. Sedangkan
pada tataran diskursus akademik, makna religion di Barat memang problematik. Hamid Fahmy
menyatakan bahwa para Sosiolog Barat mencoba mendefinisikan religion tetapi mereka gagal. F.
Schleiermacher mendefinisikan agama dengan “rasa ketergantungan yang absolut”. Demikian
pula Whithehead, agama adalah “apa yang kita lakukan dalam kesendirian”. Disini faktor-faktor
terpentingnya adalah emosi, pengalaman, intuisi dan etika. Tapi definisi ini hanya sesuai untuk
agama primitif yang punya tradisi penuh dengan ritus-ritus, dan tidak cocok untuk agama yang
punya struktur keimanan, ide-ide dan doktirn-doktrin9.
Bagi sosiolog dan antropolog, religion sama sekali bukan seperangkat ide-ide, nilai atau
pengalaman yang terpisah dari matriks kultural. Emile Durkheim malah yakin bahwa masyarakat
itu sendiri sudah cukup sebagai faktor penting bagi lahirnya rasa berketuhanan dalam jiwa. Tapi
8 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php (‘agama’) 9 Hamid Fahmy dalam Agama. Majalah Islamia Thn.1 No.3, hlm. 115-116
bagi pakar psikologi agama justru harus diartikan dari faktor kekuatan kejiwaan manusia
ketimbang faktor faktor sosial dan intelektual10.
II.1. Agama dan Religion sebagai Sinonim Al-Diin
Religion (Inggris) dan Religie (Belanda) berasal dari kata Latin: relegere (to treat carefully),
relegare (to bind together), religare (to recover). Definisi-definisi tersebut berkembang ditangan
para Filsuf, Sosiolog, dan Psikolog Barat. Mereka semua tidak memiliki kata sepakat atau
menemukan rumusan yang tepat untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Religion atau
Religie. Padahal para Sosiolog tidak mempunyai definisi yang mumpuni untuk menjelaskan
konsep Religion11.
Istilah Agama berasal dari kata Sansekerta: A-Gama (tidak kacau) atau Ã-Gam-a (jalan/ cara;
menuju Tuhan). Istilah ini awalnya digunakan oleh masyarakat Hindu di Nusantara bersamaan
dengan istilah ‘neraka’ dan ‘surga’. Setelah Islam masuk dan mengislamkan Nusantara-
Indonesia, istilah ini tetap digunakan oleh masyarakat. Hanya saja, makna istilah tersebut diganti
sesuai dengan keyakinan ummat Islam12. Sayangnya, ketika proses penggantian makna
(islamisasi bahasa) tersebut belum sempurna, Peradaban Barat menjajah Nusantara-Indonesia.
Mereka memperkenalkan istilah ‘religion’ yang kemudian digunakan oleh kaum terpelajar
dengan serapan ‘religi’13. Asimilasi ini menyebabkan istilah religion = agama = Diin.
Endang Saifudin Anshari berpendapat, arti teknis kata Diin (Arab), Religion (Inggris), Religie
(Belanda), Agama (Indonesia) adalah sama14. Sementara itu, menurut Naquib Al-Attas istilah
10 Hamid Fahmy dalam Agama. Majalah Islamia Thn.1 No.3, hlm. 116 11 M. Ridho, Meninjau Kembali Istilah “Agama”. http://komunitas-nuun.blogspot.com/2010/01/meninjau-kembali-istilah-agama.html (diakses 8 Agustus 2012) 12 Baca Selengkapnya, Sidi Gazalba, Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama. -- Jakarta: Bulan Bintang, 1978 13 Bangsa Barat awalnya menyebut orang diluar Kristen sebagai penganut Animisme dan Paganisme sebagai bentuk penolakan atau penghinaan terhadap selain mereka. Lihat, Muhammad Naquib Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, hlm.9-10. 14 Kesimpulan Anshari diatas lahir sebagai bentuk kritik beliau terhadap orang yang berusaha memisahkan dan memilih satu istilah untuk satu kebudayaan/ peradaban saja. Anshari menolak orang yang menyatakan bahwa “islam tidak bisa disebut sebagai agama atau religion, demikian juga sebutan ‘Diin’ hanya diperutukan bagi Islam saja”. Argumentasi beliau didasarkan bahwa agama selain Islam pun disebut sebagai Diin oleh Al-Qur`an.
Menurut Endang Saifudin Anshari, yang membedakan penyebutan bahwa yang dimaksud Diin itu adalah Islam atau bukan adalah kata yang menyertainya. Misalnya, Diin `l-Haqq, Diinu `l-Qayyim dan Diinu `lLah. Beliau juga menyanggah orang yang berpendapat bahwa artikel “al” pada kata “Diin” (isim ma`rifah) menunjukkan kepada Islam dengan alasan bahwa hanya ada satu disisi Allah (Surah 3:3). Beliau berdalil dengan surah as-Shaff ayat 9 dan
bahasa Arab yang tepat untuk kata religion sebagaimana dipahami dan dipraktikan di Barat dan
di timur adalah millah dan bukan Diin15. Istilah Diin dalam bahasa Arab kaya akan pengertian,
dimana tidak dapat dibatasi dengan istilah religion/ agama saja.
Islam, sebagaimana diperkenalkan oleh Al-Qur`an ialah sebuah al-Diin. Ada banyak ayat yang
menyebut istilah Diin dengan makna yang beragam. Dalam surah al-Fatihah istilah Diin
digunakan sebagai Pembalasan atau Akhirat. Sedangkan dalam surah Yusuf, istilah Diin
digunakan sebagai Undang-Undang/ Peraturan. Banyak ayat Al-Qur`an dan Hadith yang
menjelaskan kepada kita cakupan medan makna al-Diin. Kamus Al-Munjid, menerjemahkan
Ad-Diin (Jama`: Adyan) menjadi: (1) Al-Jaza wa `l-Mukafaah; (2) Al-Qadha; (3) Al-Malik/al-
Mulk wa `s-Sulthan; (4) At-Tadbir; (5) Al-Hisab. Moenawar Chalil dalam bukunya Definsi dan
Sendi Agama mengatakan:
Kata ‘Diin’ itu mashdar dari kata kerja ‘daana’ - ‘yaDiinu’. Menurut lughat, kata ‘Diin’ itu
mempunyai arti bermacam-macam, antara lain berarti: 1) Cara atau adat kebiasaan. 2)
Peraturan. 3) Undang-undang. 4) Tha`at atau patuh. 5) Menunggalkan ketuhanan. 6)
Pembalasan. 7) Perhitungan. 8) Hari Qiyamat. 9) Nasehat. 10) Agama.16
Menurut kitab Qamus al-Muhieth (karya Fairuzzabad) menerangkan, bahwa ‘Diin’ itu
mempunyai arti bermacam-macam, antara lain juga berarti: kemenangan, perjalanan, paksaan
dan peribadatan. Menurut Al-Attas, pengertian primer dari terma Diin dapat disarikan menjadi
empat konsepsi utama: keberhutangan (indebtedness), penyerahan diri (submissiveness),
kekuatan hukum (judicious power), dan kecenderungan atau tendensi alamiah.17 Lebih jelas lagi,
Al-Attas menjelaskan keterkaitan antara pengertian-pengertian tersebut secara konseptual:
Perkataan din berasal dari akar kata DYN dalam bahasa Arab yang memiliki banyak
pemaknaan yang walaupun sepertinya bertentangan satu sama lain, namun sebenarnya
memiliki hubungan secara konseptual, maka keseluruhan makna tersebut membentuk suatu
kesatuan makna yang tidak terpisahkan. ‘Keseluruhan’ yang saya maksud disini adalah apa
surah al-Kaafirun, bahwa kata “`ala `d-Diini kullihi” dan “lakum Diinukum waliya Diin” merujuk kepada Diin selain Islam14. Secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa penggunaan istilah tidak ditunjukkan dengan asal usul sejarah kebudayaannya.
15 Majalah ISLAMIA. Di Balik Paham Pluralisme Agama. -- Tahun I No.3, September – November 2004, hlm. 54 16 Lihat, http://komunitas-nuun.blogspot.com/2010/01/meninjau-kembali-istilah-agama.html (diakses 9 Des 2012) Lihat juga, Buku Ajar Agama Islam | Untuk Kalangan Mahasiswa STIKOM Banyuwangi., hlm.53 17 Majalah ISLAMIA Tahun I, No.3., hlm. 52
yang digambarkan sebagai agama Islam yang padanya terkandung segala makna yang
berkaitan, yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep din. Oleh karena kita membahas
konsep Islam yang dihubungkan dengan realitas yang secara mendalam dan erat hidup
bersama-sama pengalaman dan kehidupan manusia, berbagai makna asa yang pada
zahirnya bertentangan sebenarnya bukan berasal dari kekaburan konsep, justru merupakan
gambaran pertentangan yang terdapat dalam kehidupan manusia, yang secara erat
tercermin dalam makna-makna tersebut. Kekuatan makna-makna ini untuk
menggambarkan hakikat manusa merupakan bukti yang jelas akan kejernihan, ketelitian
dan keasliannya dalam mengungkap kebenaran. [Islam dan Sekularisme: hlm.63-64]
Jika ditelusuri medan makna dari kata al-Diin, tentu akan didapati makna al-madinah yang
merupakan “ism makan” dari al-Diin (nama tempat –dari Diin). Sedangkan tamaddun yang
merupakan sinonim dari hadlarah (kebudayaan/ peradaban) juga merujuk pada al-Diin. Jika al-
madinah merupakan “sebutan untuk tempat diberlakukannya al-diin”, sangat penting melihat
hubungan antara kedua konsep ini. Al-Attas menjelaskan:
Kepentingan sedapat mungkin harus dilihat dalam makna perubahan nama kota yang
semula dikenal sebagai Yathrib menjadi al-Madinah: Kota-besar –atau lebih tepat,
Madinatu’l-Nabiy: Kota-besar Nabi –yang terwujud segera setelah Nabi Saw.
melakukan hijrah yang bersejarah dan bermukim disana. Masyarakat Muslim yang
pertama dibangun disana pada waktu itu, dan hijrah itulah yang menandai era baru
dalam sejarah manusia. Kita harus melihat hakikat bahwa al-Madinah disebut dan
dinamakan demikian karena disanalah din yang benar-benar tegak untuk umat manusia.
Disana orang yang berimana menghambakan diri dibawah otoritas dan kuasa hukum
Nabi Saw., dayyan-nya; disanalah kesadaran berhutang dengan Allah mengambil
bentuknya yang pasti, dan cara serta kaidah pembayarannya yang disetujui mulai
diterangkan dengan jelas. Kota Nabi memberi makna tempat dimana din yang
sebenarnya dilaksanakan dibawah otoritas dan kuasa hukumnya. [hlm.65 ; footnote
no.50]
Dengan demikian, jika penggunaan istilah Agama dirujuk kepada al-diin, dan istilah Negara
dirujuk kepada al-madinah, tentu kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan istilah “agama
Islam” dan “negara Islam”. Demikian pula, problem pertentangan antara agama dan negara,
insya Allah tidak akan muncul.
III. Pluralisme Agama dan Negara
Para ahli dari berbagai disiplin ilmu di Barat cenderung menganggap agama sebagai entitas yang
komprehensif dan totalitarian, seperti definisi Greertz tentang agama atau Paul Tillich, seorang
filosof dan teolog Kristen, yang mendefinisikan agama sebagai the ultimate concern (pusat
perhatian)18. Dengan definisi yang all embracing ini, seluruh agama formal-tradisional yang
dikenal manusia, dan juga isme-isme modern yang dewasa ini tengah merebut lahan dan pasar
agama-agama tradisional dapat diakomodasinya.
Dalam perspektif Islam –sebagaimana dijelaskan dalam konsep al-diin, tak ada perbedaan
mendasar antara agama teistik dan non-teistik. Sebab konsep theos (tuhan atau ilah) menurut
perspektif Al-Quran adalah obyek sesembahan (al-ma’luh) dan penghambaan atau ibadah (al-
ma’bud). Dan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari yang satu ini di mana saja dan kapan
saja, hatta ketika dia secara terang-terangan mengingkarinya dan menafikan wujudnya (dalam
hal ini, ateis). Dalam kondisi seperti ini, pada hakikatnya para ateis umumnya telah meng-ilah-
kan apa yang Al-Quran menyebutnya: al-hawa mereka sendiri. Begitu juga tak ada bedanya
antara mengklasifikasi agama ke dalam personal dan ecclesial, atau agama alternatif, quasi-
religion (semi-agama), falsafah hidup (worldview atau weltanchauung) dan sebagainya19.
Demikian juga tidak ada bedanya, antara mencampur dua doktrin teologi atau mengabungkannya
dengan ideologi politik atau falsafah tertentu.
III.1. Agama dan Politik
Setelah kita mengetahui sifat dan karakteristik agama, bahwa ia mencakup segala sesuatu dan
mengatur segala aspek kehidupan. Tentu saja kehidupan publik atau yang sering disebut dengan
politik ada didalam cakupan agama. Senanda dengan hal itu adalah apa yang ditulis oleh seorang
pastur, Algernon Sidney Crapsey pada buku Religion and Politics20:
18 Anis Malik, hlm. 146 19 Ibid 20 Ibid, 147
In the great majority of American minds this assertion that politics is not religion
would have the force of self-evidant axiom; and yet the whole history of the world
proves that while religion is much more than politics yet politics is religion.
(Dalam pikiran mayoritas bangsa Amerika penegasan bahwa politik bukan agama
adalah diyakini sebagai suatu aksioma; akan tetapi sejarah dunia secara keseluruhan
membuktikan bahwa sementara agama lebih dari sekedar politik namun politik
adalah agama)
Crapsey juga menguatkankan pendapatnya dengan ucapan Woodrow Wilson yang menganggap
seluruh kehidupan politis pemerintahan polis Yunani kuno sebagai agama21. Bahwa politik atau
ideologi politis adalah agama ternyata bukan monopoli pendapat Crapsey. Teolog Kristen,
Dewick, menyebutkan dalam The Christian Attitude to Other Religion bahwa ideologi-ideologi
politik modern seperti komunisme, Fasisme, nasionalisme dan imperialisme sebagai “agama
politik” (polical religion)22.
Brevard Hand dalam artikel berjudul Smith v. Board of Education: Secular Humanism and
Religious Establishment menyebut “humanisme sekular” sebagai agama. Alasannya, humanisme
sekular merefleksikan seluruh karakteristik dasar agama: seperti totalitarian dan komprehensif,
yang mana tak satupun aspek kehidupan yang luput dari otoritasnya23. Ketika menyanggah kaum
kaum humanis sekular Hand, seperti dikutip oleh Anis Malik Thoha dalam Tren Pluralisme
Agama mengatakan24:
“... Bagaimanapun, mengklain bahwa tidak ada sesuatu yang riil di luar data yang bisa
diamati adalah membuat suatu asumsi berdasarkan bukan pada ilmu pengatahuan akan tetapi
pada keimanan, yaitu keimanan bahwa data yang dapat diamati adalah segala sesuatu yang
riil. Suatu pernyataan bahwa tidak terdapat hakikat yang transenden dan supernatural adalah
sebuah pernyataan religius.
Tuntutan bahwa harus ada bukti fisik mengenai supernatural, dan klaim bahwa tak adanya
suatu bukti berarti supernatural tidak bsia diterima, adalah menciptakan suatu kredo
21 Ibid 22 Ibid, 148 23 Ibid 24 Ibid, 149
keagamaan. Adalah tidak saintifik untuk mengatakan bawha karena tidak ada bukti fisik
mengenai supernatural, maka kita mesti mendasarkan teori-teori moral pada ketidakimanan
(disbelief) dan skeptisisme.” [Lihat, Arthur, Joh, dan Shaw, William H. (eds), Social &
Political Philosophy, hal 267]
Tokoh pengusung humanisme-sekular juga menyebut ideologi mereka sebagai Religon without
Revelation atau agama yang bisa eksis tanpa wahyu. Agama ini bersandarkan pada pengetahuan
saintifik dan kekuatan rasional yang empiris. Julian Huxley bahkan dengan penuh keyakinan
berpendapat bahwa “Evolutionary Humanism” adalah agama universal yang mungkin bisa
mempertemukan seluruh kepentingan manusia yang saling bertentangan25.
Menurut Anis Malik, humanisme-sekular sebagai agama baru telah menjadi ruh bagi agama-
agama baru lainnya seperti, agama sipil (civil religion) dan agama mitos (mythological
religion)26. Konsep agama sipil ini adalah contoh “agama tanpa wahyu” yang berusaha mengatur
seluruh kehidupan manusia, mulai dari keyakinan sampai persoalan hubungan antara bangsa.
III.2. Agama Sipil (Civil Religion) dan Sekularisme
Istilah Civil Religion atau Agama Sipil dipopulerkan oleh seorang Sosiolog Amerika, Robert N.
Bellah melalui artikelnya yang berjudul ‘Civil Religion in America’. Menurut Anis Malik, yang
meluncurkan istilah ini dan menteorikannya adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf berkebangsaan
Perancis. Rousseau membuat teori tentang keyakinan agama sipil yang sederhana (eksistensi
tuhan, kehidupan masa depan, pahala dan siksa, dan penolakan intoleransi)27.
Bentuk dari Agama Sipil ini sangat beragam. Secara teknis, para pemerhati dan peneliti berbeda
pendapat dalam rumusannya. Akan tetapi secara umum, istilah ini menunjuk pada fenomena
yang mereka sebut “a new kind of national religiousness”. Didalam diskursus ini muncul istilah
“American Way of Life (oleh Will Herberg),”Religion of the Republic (oleh Sidney E. Meat),
“Public Religion” (oleh Benjamin Franklin), dan sebagainya. Untuk mencakup seluruh istilah
25 Ibid, 148 26 Ibid, 149 27 Teks aslinya tertulis: The phrase "civil religion" is, of course, Rousseau's. In chapter 8, book 4 of The Social Contract, he outlines the simple dogmas of the civil religion: the existence of God, the life to come, the reward of virtue and the punishment of vice, and the exclusion of religious intolerance. All other religious opinions are outside the cognizance of the state and may be freely held by citizens. [Lihat, Biblical Religion and Civil Religion in America by Robert N. Bellah. http://hirr.hartsem.edu/Bellah/articles_5.htm]
tersebut berikut pengertiannya, maka Robert Nisbert mendefiniskan Agama Sipil sebagai “the
religious or quasi-religious regard for certain civic values and traditions found recurrently in
the history of the political state.” (penghormatan religius atau semi-religius terhadap nilai dan
tradisi ketatanegaraan yang ditemukan berulangkali terjadi dalam sejarah negara politik)28.
Menurut Donald Jones, Agama Sipil mewujud ketika mayoritas penduduk suatu negara atau
daerah mendeskripsikan the ultimate reality pada dimensi-dimensi masyarakat politis mereka,
seperti nilai-nilai sosial atau pranata pemerintahan; dan ketika mereka meyakini bahwa sumber
makna bagi sejarah dan tata sosial mereka adalah sakral; dan ketika keyakinan ini diekspresikan
melalui ritual-ritual kerakyatan, mitos, simbol, dan sejumlah keyakinan yang disakralkan29.
Adanya kontroversi dan perbedaan pendapat seputar hakikat Agama Sipil, menurut Anis Malik
menggambarkan dengan jelas betapa kompleksnya fenomena agama sipil ini, sekaligus
menegaskan secara meyakinkan bahwa fenomena ini memang benar-benar ada. Bellah dalam
artikelnya mengatakan:
“Sementara sebagian orang berargumen, bahwa Kristen adalah agama nasional, dan
yang lain (berargumen), bahwa gereja dan sinagog hanyalah meramaikan agama
yang digeneralisasi (kedalam) “Pandangan Hidup Amerika),” sedikit sekali orang
yang merasakan bahwa secara aktual bersama gereja ada pula agama sipil – yang
cukup jelas perbedaannya – yang terejawantah dan terlembagakan dengan baik di
Amerika.” [Lihat, Bellah, Robert N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-
Traditonal World , hlm. 168, seperti dikutip oleh Anis Malik: hlm. 152]
Dalam artikel tersebut Bellah mengukuhkan keberadaan Agama Sipil di Amerika. Jika
pengertian “a new kind of national religiousness” dapat diterima, maka akan dengan mudah
menemukan genealogi dan titik tolak munculnya agama ini, yakni paham pluralisme agama dan
politik30. Tumbuh dan berkembangnya pluralisme agama dalam aspek politik mendapat
momentum ketika merebaknya revolusi sosial dan konflik yang memunculkan krisis religious
disorientation. Sementara itu, disaat yang bersamaan agama-agama yang ada tidak mampu
memainkan perannya dalam kontestasi persatuan bangsa dan perjuangan rakyat. Akhirnya,
28 Anis Malik, 151 29 Ibid, 151-152 30 Ibid, 153
revolusi politik merumuskan dasar-dasar kehidupan yang baru berupa nasionalisme (nation-
state). Setelah itu, kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh sistem dan pranata yang lahir
dari ideologi politik, lengkap dengan segala atribut, simbol-simbol sakral, ritual upacara dan teks
suci yang menjadi acuan hukum. Orang-orang yang mengalami religious disorientation akan
dengan mudah berpaling kepada agama baru ini. Kemudian mereka akan membuang sedikit-
sedikit (atau sekaligus) agama lama mereka. Hal itu, karena tradisi dan keyakinan lama mereka
dianggap telah out of date atau usang serta mampun menyulut perpecahan (tidak mampu
mempersatukan masyarakat).
Berdasarkan pemaparan diatas, Ernest Gellner berkesimpulan bahwa civil religion merupakan
saingan agama-agama tradisional dan menggantikan kedudukannya31. Oleh karena itu,
pluralisme politik seperti ini disebut juga sebagai “a normative doctrine”, karena ia telah menjadi
referensi utama bagi semua perilaku manusia, dan strandar atau ukuran baik dan buruk, benar
dan salah, haq dan batil, boleh dan dilarang, dan nilai-nilai lainnya.
Agama sipil yang sinkretik semacam ini agaknya lebih diterima di negara yang menggunakan
sistem demokrasi hasil import dari Amerika. Paling tidak, inilah yang ada di Indonesia. Adanya
indikasi kuat marjinalisasi agama-agama tradisional secara massif dan sistemik dari pentas
politik adalah wujud dari upaya menggantikan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat
dengan Agama Sipil yang diadopsi oleh negara. Dalam hal ini, Pancasila pernah diusung oleh
para penganjur pluralisme dan humanisme-sekular sebagai agama sipil di Indonesia. Melalui
lembaga BP – 7, pancasila pernah di-ideologisasi, glorifikasi dan didakwahkan sebagai ‘the
ultimate concern’.32 Secara singkat dapat disebutkan bahwa agama sipil di Indonesia ini sangat
mirip dengan agama sipil di Amerika33. Perdebatan (atau lebih tepatnya penyelewengan)
mengenai sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kasus ideologisasi Pancasila merupakan
31 Ibid, 154 32 Kita bisa melihat upaya ini dalam buku PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI (dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara). Buku ini merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam seminar “Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” yang dilaksanakan oleh Kelompok Studi Pengembangan Pemikiran Pancasila dan UUD 1945 BP-7 Pusat tanggal 24 – 26 Oktober 1989 di Jakarta. Dalam buku ini Pancasila diposisikan sebagai paham intergralistik, ideologi terbuka dan pandangan-hidup.
fenomena perkembangan agama sipil di Indonesia. Nurcholish Madjid dalam salahsatu
artikelnya pernah menyatakan bahwa Pancasila adalah kalimah sawa yang harus didakwahkan34.
Anis Malik Thoha menyimpulkan bahwa agama lokal (mayoritas yang dominan) merupakan
unsur utama dalam komposisi agama sipil35. Oleh karena itu warna dan aroma Islam dalam
agama sipil di Indonesia akan tampak dominan, persis seperti dominannya warna dan aroma
Protestan dalam agama sipil Amerika. Agama sipil yang lahir dan berkembang di Amerika
Serikat hanyalah satu contoh soal. Agama model ini dapat lahir dan berkembang di belahan
dunia mana pun yang mengadopsi demokrasi. Bentuk variasi agama sipil memang berbeda-beda,
tapi hakikat dan esensinya tetap sama, khususnya dalam menuhankan (apoteosisasi) kehidupan
politik kebangsaan dan menganggapnya di atas segala-galanya. Dalam perspektif keagamaan
tradisional, menurut beberapa pengamat merupakan bentuk lain dari “paganisme”.
Jika kita membahas demokratisasi sebagai upaya penyebaran paham pluralisme agama dan
secara khusus Agama Sipil, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kedua hal tersebut persoalan
sekularisme. Sebab, demokrasi merupakan wujud sistem politik akibat dari sekularisme.
Demikian juga, sekularisme sangat terkait erat dengan pluralisme agama. Sekularisme menuntut
dimarjinalkannya agama tradisional dalam ruang publik. Disaat yang bersamaan diciptakanlah
ideologi politik untuk mengatur kehidupan publik. dan Lantas, apakah sekluarisme yang
menyebabkan timbulnya teori pluralisme agama, atau sebaliknya?
Menurut Anis Malik, pluralisme agama, pluralisme politik (demokrasi) dan globalisasi adalah
akibat dan sekaligus bagian dari proses sekularisasi36. Hal ini akan semakin tanpak jelas jika kita
menyandingkan konsep ‘Public Religion’ Benjamin Franklin, ‘Republican Banquet’ William
James, ‘Common Faith’ John Dewey dan ‘Secular City’ Harvey Cox37.
Sekularisme, seperti juga Pluralisme Agama bisa saja dianggap tidak bertentangan atau tidak
memusuhi agama-agama yang ada. Karena setiap dalam sebuah negara yang mewujudkan
Agama Sipil, agama-agama tradisional masih bisa tumbuh (meskipun terbatas). Bahkan beberapa
agama yang beruntung bisa menjadi agama resmi/ legal yang boleh dianut oleh warga negara
33 Anis Malik, 160 34 Ibid, 160 - 161 35 Ibid, 161 36 Ibid, 134 37 Ibid
tersebut. Demikian juga dalam negara yang sekular aktivitas peribadatan agama-agama
tradisional masih bisa berjalan dengan baik di tempat ibadah. Bahkan seorang pengusung
sekularisme radikal sekalipun, bisa saja ia merupakan orang yang rajin beribadah di masjid atau
gereja. Masyarakat yang sekular pun masih bisa meramaikan tempat-tempat ibadah agama
formal mereka. Oleh karena itu, Ninian Smart mengatakan bahwa pluralisme agama adalah
merupakan salah satu arti sekularisme.
IV. Penutup
Hubungan antara agama dan negara seringkali menimbulkan pro-kontra. Kalangan Islamis
tentunya akan selalu mendasarkan setiap persoalan -termasuk negara pada- pijakan agama.
Sementara kalangan Sekularis walau bagaimanapun tidak bisa membuang agama dalam
kehidupannya. Bahkan, betapa pun sempitnya ruang untuk agama yang diberikan oleh kalangan
Sekularis, undang-undang (wadl`iyyah) tetap membutuhkan agama dan ketuhanan untuk
mengambil kesaksian atau sumpah jabatan kepala negaranya. Hal ini menunjukan bahwa
manusia tidak bisa meninggalkan ghorizah taddayun (hasrat glorifikasi) terhadap Tuhan dan
agama.
Dalam perspektif Islam, posisi agama terhadap keberadaan negara adalah mabda` (dasar/
ideology) dan ma`ad (tujuan/ vision) secara sekaligus. Negara diadakan karena keimanan kepada
Allah SWT dan kepatuhan kita terhadap Undang-undang-Nya. Demikian pula, ‘negara’
diselenggarakan untuk mencapai mendapatkan pahala (ajr-l hasanah) dan keridhoan Allah SWT.
Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Iqtishad fil I`tiqad menyimpulkan bahwa nidzam al-diin tidak
akan baik kecuali dengan nidzam al-dunya. Bahkan beliau menjadikan nidzamu al-dunya sebagai
syarat (shartun) kepada nizdami al-diin. Betapa erat dan terkaitnya hubungan diantara agama dan
negara.
Perdebatan yang sering muncul adalah masalah penerjemahan istilah Madinah secara kontekstual
dan politis. Sebagian menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai Madinah adalah sebuah
‘negara modern’ dalam pengertian kekuasaan konstitusional. Sementara sebagian lagi
mengusung istilah ‘masyarakat madani’ dan mengasimilasikannya dengan konsep ‘civil society’.
Jika kita ingin memahami istilah ‘Madinah’ dengan baik, kita bisa merujuk kepada perspektif
bahasa, sejarah, dan tentu saja al-Qur’an dan al-Hadith.
Dalam konteks hijrah, Yastrib adalah mahjar (tempat tujuan hijrah), sedangkan tujuan hijrah
mereka menuju mahjar adalah untuk iqamatud-diin. Oleh karena itu menjadi tepatlah ketetapan
Nabi Muhammad SAW untuk menamakan mahjar mereka sebagai al-Madinah.
Kesimpulannya, paham pluralisme agama dalam hal ini mazhab humanisme-sekular
menganggap bahwa agama dilahirkan dari kebudayaan nasional suatu negara-bangsa. Agama ini
adalah agama nasional yang bersifat politis dan dianggap bisa eksis tanpa wahyu. Sedangkan
dalam perpsektif Islam, ketika agama (diin) diterapkan secara sempurna di suatu tempat atau
wilayah maka tempat tersebut adalah negaranya (madinah). Mafhum mukhalafah-nya, negara
adalah sebutan atau lambang dari kesempuraan penerapannya suatu agama. Oleh karena itu,
setiap negara lahir dari penerapan agama dan penyempurnaannya disuatu tempat. Jika demikian
persoalannya, agama apakah yang diterapkan di Indonesia? Waallahu a`lam!
BIBLIOGRAFI
BP – 7 Pusat, Pancasila Sebagai Ideologi (Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa Dan Bernegara). 1992
Dr. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis. Jakarta: Perspektif, 2005.
Dr. Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial.
Jakarta: Kencana, 2010.
Huston Smith, Agama-Agama Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
KBBI Online. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
M. Ridho, Meninjau Kembali Istilah “Agama”. http://komunitas-
nuun.blogspot.com/2010/01/meninjau-kembali-istilah-agama.html (diakses 9 Desember
2012)
M. Ridho, Perspektif Hubungan Negara dan Agama. http://komunitas-
nuun.blogspot.com/2010/01/perspektif-hubungan-negara-dan-agama.html (diakses 9
Desember 2012)
Majalah Islamia, Di Balik Paham Pluralisme Agama. Thn. 1 No.3, September – November 2004
Prof. Dr. H.M. Rasjidi, Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi. Depok: Kalam Ilmu
Indoneisa, 1432/2001.
Robert N. Bellah, Biblical Religion and Social Science in the Modern World.
http://www.robertbellah.com/articles_1.htm (diakses 9 Desember 2012)
Robert N. Bellah, Civil Religion in America. http://www.robertbellah.com/articles_5.htm
(diakses 9 Desember 2012)
Sidi Gazalba, Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama. -- Jakarta: Bulan Bintang,
1978
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dan Sekularisme. Bandung: PIMPIN, 2010.