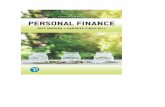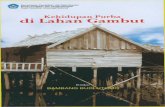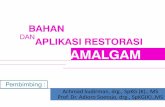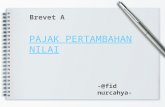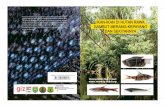LAPORAN - KMS Troper - Badan Restorasi Gambut
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LAPORAN - KMS Troper - Badan Restorasi Gambut
LAPORAN
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut di KHG S. Saleh - S. Sugihan
dan KHG S. Sebumbung - S.Batok Kabupaten Ogan Komering Ilir
TIM PELAKSANA
Ketua Tim: Ir. Muhammad Yazid, M.Sc., Ph.D. Anggota: Prof. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr., Ph.D.
Dr. Agr. Ir. Erizal Sodikin . Dr.Ir. M.Umar Harun, MS Ir. Nura Malahayati M.Sc., Ph.D. Dr. Dessy Adriani, SP., M.Si
KERJASAMA ANTARA BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2018
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama antara Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Universitas Sriwijaya dengan judul ”Kajian
Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut di KHG S. Saleh - S. Sugihan dan KHG S. Sebumbung - S.Batok Kabupaten Ogan Komering Ilir” dapat
diselesaikan.
Kebakaran lahan dan hutan di lahan gambut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Upaya penanggulangannya sudah lama dilakukan tetapi keberhasilannya belum menunjukkan hasil memuaskan. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap yang menganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara. Dampak kebakaran hutan terhadap produksi pertanian menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya. Kebakaran hutanpun menghasilkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer.
Untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di lahan gambut, perlu dilakukan dengan berbagai upaya seperti yang telah dicanangkan oleh Badan Restorasi Gambut dengan Program 3R (Rewetting, Revegetation, Revitalization Livelihoods). Dalam rangka mendukung keberhasilan program Revitalization Livelihoods, perlu didahului riset. Kerjasama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG) dengan Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan riset dan Pilot Project tahun 2017 memberikan hasil yang nyata dan terukur. Riset komoditas lokal potensial di lahan gambut, pilot project terintegrasi dan paludikultur berhasil mengembangkan dan merekomendasikan beberapa tanaman lokal potensial untuk restorasi lahan gambut. Sebagai komoditas indigen lahan gambut dan telah diusahakan masyarakat secara terbatas di beberapa tempat, maka beberapa komoditas potensial tersebut seyogyanya diteliti dan dikembangkan lebih lanjut karena dapat berkontribusi pada restorasi lahan gambut sekaligus menambah sumber pendapatan masyarakat.
Sebagai kelanjutan dari Pilot Project tahun 2017, pada tahun 2018 BRG dan Universitas Sriwijaya melaksanakan “Kajian Profitabilitas dan Keekonomian
Komoditi Ramah Gambut di KHG S. Saleh - S. Sugihan dan KHG S. Sebumbung - S.Batok Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Kajian ini meliputi 5 kegiatan, yaitu (1) Kajian Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa, (2) Pengembangan Biomas Pakan Kerbau, (3) Kajian Tingkat Konsumsi Rumah Tangga, (4) Analisis Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau Rawa, (5) Analisis Profitabilitas dan Keekonomian Tanaman Paludikultur. Diharapkan dengan hasil kajian ini beberapa persoalan terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah gambut dapat diimplementasikan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI ii
dalam kegiatan nyata di lapangan untuk mendorong kemandirian masyarakat membangun wilayah gambut di sekitar mereka.
TIM PENELITI
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2. Permasalahan .................................................................................................. 3
1.3. Tujuan ............................................................................................................. 3
1.4. Luaran ............................................................................................................. 4
1.5. Kerangka Kerja Logis ..................................................................................... 4
II. KERANGKA PEMIKIRAN .......................................................................... 7
2.1. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 7
2.2. Model Pendekatan Penelitian ........................................................................ 23
III. METODE PENELITIAN ............................................................................ 24
3.1. Waktu dan Tempat .......................................................................................... 24
3.2. Metode Pendekatan ......................................................................................... 25
3.3. Pelaksanaaan Kajian ....................................................................................... 26
3.4. Metode Pengumpulan Data ............................................................................ 26
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ............................................................ 28
IV. Analisis Profitabilitas dan Kekonomian Kerbau Rawa ........................... 30
4.1 Pemeliharaan Kerbau Rawa ........................................................................... 30
4.1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 30
4.1.2. Tujuan .......................................................................................................... 31
4.1.3. Metode Pelaksanaan .................................................................................... 31
4.1.4. Profil Petani Pemeliharaan Kerbau Rawa ................................................... 31
4.1.5. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa ................................................... 42
4.1.5.1. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Desa P. Layang ...................... 43
4.1.5.2. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Desa Bangsal .......................... 45
4.1.5.3. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Desa Kuro .............................. 48
4.1.5.4. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Desa Menggeris ..................... 51
4.1.5.5. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Desa Pampangan .................... 54
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI iv
Halaman
4.1.6. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa ..................................... 57
4.1.6.1. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok ........ 57
4.1.6.2. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual ........ 60
4.1.6.3. Analisis Sensitivitas Pemeliharaan Kerbau Rawa .................................... 62
4.2. Pengembangan Biomas Pakan Kerbau di Lahan Gambut .............................. 64
4.2.1. Latar Belakang ............................................................................................. 64
4.2.2. Tujuan .......................................................................................................... 65
4.2.3. Metode Pelaksanaan .................................................................................... 66
4.2.4. Pembuatan Demplot Kajian Biomas Pakan Kerbau di Lahan Gambut ....... 66
4.2.5. Produksi Biomas Pakan Kerbau .................................................................. 64
4.3. Kajian Konsumsi Susu dan produk Berbasis Susu ......................................... 70
4.3.1. Latar Belakang ............................................................................................. 70
4.3.2. Tujuan .......................................................................................................... 72
4.3.3. Susu dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Susu .................... 72
4.3.4. Lokasi Kajian ............................................................................................... 75
4.3.5. Metode Penelitian ........................................................................................ 75
4.3.6. Perilaku Konsumsi Susu .............................................................................. 77
4.3.7. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Susu ...................... 79
4.4. Pengembangan Pengolahan Susu Kerbau Rawa ............................................ 86
4.4.1. Latar Belakang ............................................................................................. 86
4.4.2. Tujuan .......................................................................................................... 87
4.4.3. Metode Pelaksanaan .................................................................................... 87
4.4.4. Uji Sensoris (Daya Terima) Minuman Jeli Susu Kerbau ............................ 88
4.4.4.1. Aroma ....................................................................................................... 89
4.4.4.2. Tekstur ...................................................................................................... 90
4.4.4.3. Rasa .......................................................................................................... 91
4.4.5. Analisis Kandungan Kimis Minuman Jeli Susu Kerbau Rawa ................... 92
4.4.5.1. Kadar Air .................................................................................................. 92
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI v
Halaman
4.4.5.2. Kadar Abu ................................................................................................ 92
4.4.5.3. Protein ....................................................................................................... 93
4.4.5.4. Lemak ....................................................................................................... 93
4.4.5.5. Karbohidrat ............................................................................................... 93
4.4.5.6. Kalori ........................................................................................................ 93
4.4.6. Analisis Profitabilitas Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau ....... 94
4.4.7. Analisis Sensitivitas Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau .................... 96
V. Analisis Profitabilitas dan Keekonomian Tanaman Paludikultur ............. 97
5.1. Monitoring Pilot Project Paludikultur dan Restorasi Terintegrasi ................. 97
5.1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 97
5.1.2. Tujuan .......................................................................................................... 97
5.1.3. Metode Pelaksanaan .................................................................................... 98
5.1.4. Hasil Kegiatan ............................................................................................. 98
5.1.4.1. Monitoring Hasil Kegiatan Penanaman Tahun 2017 ............................... 98
5.2. Analisis Profitabilitas dan Keekonomian Komoditas Paludikultur ................ 102
5.2.1. Latar Belakang ............................................................................................. 102
5.2.2. Tujuan .......................................................................................................... 107
5.2.3. Metode Pelaksanaan .................................................................................... 107
5.2.4. Hasil Analisis ............................................................................................... 111
5.2.4.1. Gambaran Umum Budidaya Tanaman Paludikultur ................................ 111
5.2.4.2. Pengembangan Model Paludikultur di Lahan Gambut Provinsi Sum-
atera Selatan ............................................................................................ 117
5.2.4.3. Aspek Finansial Model Tanaman Paludikultur ......................................... 129
5.2.4.4. Analisis Sensitivitas Model Tanaman Paludikultur ................................. 152
VI. Kesimpulan .................................................................................................... 155
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 158
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Deskripsi kegiatan riset dan Pilot Project tahun 2017 ....................... 2
Tabel 1.2. Kerangka kerja logis kajian profitabilitas dan keekonomian komodi- tas ramah gambut .............................................................................. 4
Tabel 2.1. Sebaran & Luas Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1990 dan Tahun 2002 ........................................................................ 9
Tabel 2.2. Kebutuhan air untuk pertumbuhan beberapa jenis tanaman di lahan gambut ....................................................................................................... 10
Tabel 2.3. Kedalaman permukaan air tanah dan ketebalan bahan organik sebagai pembatas produksi tanaman pertanian ................................. 11
Tabel 4.1. Jumlah Responden Pemelihara Kerbau Rawa di Kecamatan Pampangan ........................................................................................................... 31
Tabel 4.2. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa Desa P. Layang .................... 32
Tabel 4.3. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Bangsal ................... 34
Tabel 4.4. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Kuro ........................ 36
Tabel 4.5. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Menggeris ............... 38
Tabel 4.6. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Pampangan ............. 40
Tabel 4.7. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pulau Layang ...... 43
Tabel 4.8. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Pulau Layang .................................................................................... 44
Tabel 4.9. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Bangsal ............... 45 Tabel 4.10. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa
Bangsal ............................................................................................. 46 Tabel 4.11. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Kuro ................... 48 Tabel 4.12. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa
Kuro .................................................................................................. 50 Tabel 4.13. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Menggeris .......... 51 Tabel 4.14. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa
Menggeris ......................................................................................... 53 Tabel 4.15. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pampangan ......... 54 Tabel 4.16. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala
Desa Pampangan .............................................................................. 56 Tabel 4.17. Asumsi Investasi Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok
di Kecamatan Pampangan ................................................................. 57
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI vii
Halaman
Tabel 4.18. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan ................ 58
Tabel 4.19. NPV dan IRR Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan ................................................................ 58
Tabel 4.20. Net B/C Ratio Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan ................................................................ 59
Tabel 4.21. BEP Nilai Rupiah dan Profit Margin Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan ............................ 59
Tabel 4.22. Asumsi Investasi Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan ................................................................. 60
Tabel 4.23. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan ................ 60
Tabel 4.24. NPV dan IRR Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan ................................................................ 61
Tabel 4.25. Net B/C Ratio Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan ................................................................ 61
Tabel 4.26. BEP Nilai Rupiah dan Profit Margin Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan ............................. 62
Tabel 4.27. Analisis Sensitivitas Kemungkinan Situasi Pada Usaha Pemelihara- an Kerbau Rawa Pola Kelompok ..................................................... 63
Tabel 4.28. Analisis Sensitivitas Kemungkinan Situasi Pada Usaha Pemelihara- an Kerbau Rawa Pola Kelompok ..................................................... 63
Tabel 4.29. Spesies Rumput yang Tumbuh di Petak Perlakuan Organik, NPK dan Urea ............................................................................................ 69
Tabel 4.30. Rata – rata Konsumsi Susu Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan per bulan, Tahun 2017 ..................................................................... 71
Tabel 4.31. Perbandingan Kandungan Kimia Susu Kerbau Rawa dan Susu Sapi ................................................................................................... 73
Tabel 4.32. Frekuensi perilaku konsumsi susu Desa Bangsal, Desa Pampangan dan Desa Menggeris di Kecamatan Pampangan ............................... 77
Tabel 4.33. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Susu .................................................................................................. 80
Tabel 4.34. Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................ 81 Tabel 4.29. Asumsi Investasi Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau .... 82 Tabel 4.30. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pengolahan Minum-
an Jeli Susu Kerbau .......................................................................... 82 Tabel 4.31. NPV dan IRR Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau ......... 83 Tabel 5.1. Jumlah Tanaman yang Hidup Pada Waktu Monitoring Tahun
2018 .................................................................................................. 98
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI viii
Halaman
Tabel 5.2. Hasil Pengukuran Tanaman Jelutung pada Lokasi Pilot Project Tahun 2018 ....................................................................................... 99
Tabel 5.3. Hasil Pengukuran Tanaman Meranti pada Lokasi Pilot Project Tahun 2018 ....................................................................................... 99
Tabel 5.4. Hasil Pengukuran Tanaman Pulai pada Lokasi Pilot Project Tahun 2018 ....................................................................................... 99
Tabel 5.5. Hasil Pengukuran pH, Kedalaman Gambut dan Muka Air Tanah Pada Bulan September 2018 ............................................................. 100
Tabel 5.6. Luas Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan .............................................................................. 105
Tabel 5.7. Perbandingan Pertumbuhan Beberapa Tanaman Hutan Gambut ....... 120 Tabel 5.8. Harga Produk Hasil Hutan Kayu ........................................................ 123 Tabel 5.9. Harga Produk Hasil Hutan Bukan Kayu ............................................ 123 Tabel 5.10. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludi-
kultur Meranti-Nanas Tahun 2018 ................................................... 130 Tabel 5.11. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludi-
kultur Meranti-Cabe Tahun 2018 ..................................................... 131 Tabel 5.12. Biaya Investasi Model Paludikultur Campuran Meranti-Nanas
Tahun 2018 ....................................................................................... 134 Tabel 5.13. Biaya Investasi Model Paludikultur Campuran Meranti-Cabe
Tahun 2018 ....................................................................................... 135 Tabel 5.14. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Meranti-Nanas
Tahun 2018 ....................................................................................... 136 Tabel 5.15. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe
Tahun 2018 ....................................................................................... 137 Tabel 5.16. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran
Meranti-Nanas Tahun 2018 .............................................................. 138 Tabel 5.17. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran
Meranti-Cabe Tahun 2018 ................................................................ 138 Tabel 5.18. Analisis Finansial Model Paludikultur campuran Meranti-Nanas
Tahun 2018 ....................................................................................... 139 Tabel 5.19. Analisis Finansial Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe
Tahun 2018 ....................................................................................... 140 Tabel 5.20. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludi-
kultur Jelutung-Nanas Tahun 2018 ................................................... 141 Tabel 5.21. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludi-
kultur Jelutung-Cabe Tahun 2018 .................................................... 143 Tabel 5.22. Biaya Investasi Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas
Tahun 2018 ....................................................................................... 145
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI ix
Halaman
Tabel 5.23. Biaya Investasi Model Paludikultur campuran Jelutung-Cabe Tahun 2018 ....................................................................................... 146
Tabel 5.24. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas Tahun 2018 ....................................................................................... 148
Tabel 5.25. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Jelutung-Cabe Tahun 2018 ....................................................................................... 148
Tabel 5.26. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas Tahun 2018 ............................................................. 149
Tabel 5.27. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran Jelutung Cabe Tahun 2018 ............................................................... 150
Tabel 5.28. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Paludikultur Meranti-Nanas Tahun 2018 ......................................... 152
Tabel 5.29. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Meranti-Cabe Tahun 2018 ................................................................ 152
Tabel 5.30. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Jelutung-Nanas Tahun 2018 ............................................................. 153
Tabel 5.31. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Jelutung-Cabe Tahun 2018 ............................................................... 154
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Konsep Analisis Biaya Manfaat atau Extended Cost-Benefit Analysis (ECBA) .......................................................................................... 19
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Kajian ............................................................. 23 Gambar 3.1. Peta KHG Sungai Saleh dan Sungai Sugihan; Kabupaten Banyuasin
dan Kabupaten Ogan Komering Ilir ................................................ 24 Gambar 3.2. Peta KHG Sungai Sibumbung-Sungai Batok, Kabupaten Ogan
Komering Ilir................................................................................... 25 Gambar 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok ................... 42 Gambar 4.2. Kegiatan Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individu ....................... 42 Gambar 4.3. Pemberian Pakan Kerbau Rawa ....................................................... 43 Gambar 4.4. Bentuk dan posisi petak percobaan biomas pakan kerbau rawa ...... 67 Gambar 4.5. Kondisi pakan gembala dan rumput biomas pakan kerbau ............. 67 Gambar 4.6. Penampilan petak percobaan biomas pakan kerbau ........................ 68 Gambar 4.7. Pengamatan Spesies Rumput Saat Panen Biomas Pertama dan
Kondisi Rumputan Petak yang diberi Pupuk Organik ................... 69 Gambar 4.8. Biomas yang didapat dari Petak yang diberi Pupuk Organik dan
Biomas yang sedang dikeringkan .................................................. 70 Gambar 4.9. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas ............................... 82 Gambar 4.10. Grafik Normal P-Plot Hasil Uji Normalitas ................................... 83 Gambar 4.11. Uji sensoris (daya terima) di lab penelitian UNSRI ....................... 88 Gambar 4.12. Bahan dan hasil produk minuman jeli susu kerbau rawa ............... 88 Gambar 4.13. Uji sensoris (daya terima) terhadap anak SD di Kecamatan
Pampangan .................................................................................... 89 Gambar 4.14. Skor kesukaan aroma minuman jeli susu kerbau ............................ 89 Gambar 4.15. Skor kesukaan tekstur minuman jeli susu kerbau ........................... 90 Gambar 4.16. Skor kesukaan rasa minuman jeli susu kerbau ............................... 91 Gambar 5.1. Kondisi Areal Pertanaman .............................................................. 100 Gambar 5.2. Pertumbuhan Tanaman padi ............................................................ 101 Gambar 5.3. Pertumbuhan Tanaman Jagung ....................................................... 101 Gambar 5.4. Pertumbuhan Tanaman Nenas ........................................................ 101 Gambar 5.5. Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah .......................................... 101 Gambar 5.6. Pertumbuhan Tanaman Kangkung ................................................. 102 Gambar 5.7. Tanaman Padi dan Nanas ................................................................ 102 Gambar 5.8. Peta Rawan Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan ........................ 104 Gambar 5.9. Lokasi Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI ..... 124 Gambar 5.10. Lokasi Desa Sepucuk Kecamatan Kayu Agung Kab. OKI ............ 124 Gambar 5.11. Bentuk Gambaran Lahan Pengembangan Model Paludikultur ...... 128
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI xi
Halaman
Gambar 5.12. Pengaturan Jarak Tanam Model Paludikultur Jelutung dengan Tanaman Sela (Nanas, Cabe) ......................................................... 128
Gambar 5.13. Pengaturan Jarak Tanam Model Paludikultur Meranti dengan Tanaman Sela (Nanas, Cabe) ......................................................... 129
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kerjasama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dengan Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan riset dan Pilot Project tahun 2017 memberikan hasil yang nyata dan terukur. Riset komoditas lokal potensial di lahan gambut KHG S Saleh-S Sugihan, S Sugihan-S Lumpur, dan S Sebumbung-S Batok berhasil mendata dan merekomendasikan beberapa tanaman lokal potensial untuk restorasi lahan gambut, diantaranya Pulai, Purun dan Nipah (Tabel 1.1). Sebagai komoditas indigen lahan gambut dan telah diusahakan masyarakat secara terbatas di beberapa tempat, maka beberapa komoditas potensial tersebut seyogyanya dikembangkan karena dapat berkontribusi pada restorasi lahan gambut sekaligus menambah sumber pendapatan masyarakat.
Pilot project implementasi paludikultur telah menanami 8 hektar lahan di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam yang merupakan bagian dari KHG S Saleh-S Sugihan dengan beberapa jenis tanaman paludikultur, diantaranya Jelutung, Meranti dan Sagu. Untuk memberikan tambahan pendapatan masyarakat yang memeliharanya, maka penanaman pepohonan tersebut perlu dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman semusim yang termasuk dalam kelompok paludikultur, diantaranya nenas dan tanaman semusim lainnya.
Pilot project ujicoba restorasi gambut terintegrasi telah menanami 8 hektar lahan di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam pada KHG yang sama dengan beberapa jenis tanaman ramah gambut, diantaranya Meranti, Gelam dan Jelutung. Pengusahaan tanaman ini pun berkontribusi pada upaya revegetasi yang dikombinasikan dengan pengembangan tanaman padi dan palawija sekaligus pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian lokal.
Hasil Riset Komoditas Lokal Potensial ditemukan beberapa komoditi yang berada di lahan gambut. Potensi produksi komoditi yang dominan dari KHG SS adalah padi yaitu 36.030 ton GKP/tahun, ikan (29.201 ton/tahun), kerbau (2.320 ekor/tahun), waalet (64 kg/tahun) dan kelapa dihasilkan lebih dari 3.6 juta butir/tahun. KHG SL mempunyai produktivitas padi (50.390 ton GKP/tahun), ikan (6.222 ton/tahun), dan wallet (362 kg/tahun). KHG SB mampu memproduksi padi (127.000 ton GKP/tahun), ikan (6.396 ton/tahun), kerbau rawa (2.583 ekor), dan wallet (83 kg/tahun). Secara keseluruhan, deskripsi hasil Riset dan Pilot Project tahun 2017 secara ringkas disajikan pada Tabel 1.1.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 2
Tabel 1.1. Deskripsi kegiatan riset dan Pilot Project tahun 2017
Kegiatan Wilayah KHG
Komponen Kegiatan Cakupan/ Luas Kegia-tan
(ha)
Dampak yg Diharapkan (ha)
Komoditas terkait
Riset Komoditas Lokal Potensial
S Saleh-S Sugihan, S Sugihan-S Lumpur S Sebumbung-S Batok
Invetarisasi jenis komoditi potensial di 3 KHG
Estimasi potensi biologi dari berbagai komoditi potensial di 3 KHG
Inventarisasi HHBK di 3 KHG
100 desa dalam wilayah 13 kecamatan dalam Kab. OKI dan Banyuasin
Peningkatan kepedulian dan arti penting keberadaan KHG untuk masyarakat di dalam wilayah KHG
Pulai Purun Nipah Kantong
Semar Terantang Tarok
Kelapok Prepet Simpur Gadung Kerbau
Rawa, Padi rawa Walet Kelapa Ikan
Pilot Project Restorasi Gambut berbasis Paludikultur
Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI. KHG S Saleh-S Sugihan
Pemasangan sekat kanal
Penanaman Pemeliharaan
8 Peningkatan muka air tanah dan pertumbuhan tanaman untuk restorasi gambut
Jelutung Meranti Sagu Nanas
Pilot Project Restorasi Gambut Terintegrasi
Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI. KHG S Saleh-S Sugihan
Penanaman komoditas bernilai ekonomi
Pembuatan petak percontohan
Pengaturan sistem tanam
8 Peningkatan muka air tanah dan pertumbuhan tanaman untuk restorasi gambut
Meranti Merah
Gelam Jelutung Pulai Meranti
Kijang Padi Sagu
Sumber: Laporan Riset dan Pilot Project kerjasama BRG dan Unsri tahun 2017
Selanjutnya hasil Riset mata pencaharian, menemukan bebarapa hal sebagai berikut Berdasarkan hasil riset tahun 2017, diketahui bahwa Komoditas yang akan dikembangkan ada 4 komoditas unggulan di lahan gambut yaitu:
1. Padi rawa (B/C = 0,9) 2. Purun
Tikar Purun (B/C = 0,72) 3. Susu Kerbau Rawa
Gulo Puan (B/C=0,72) Susu segar (pasteurized fresh milk) dan susu segar berperisa (flavored
milk) (B/C = 1,42) Minuman yoghurt (yoghurt beverages) (B/C = 0,19) Es krim (soft ice cream) (B/C = 0,09)
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 3
Permen susu karamel (caramel milk candy) (B/C = 1,10) 4. Ikan
Ikan Asin (B/C =0,082) Ikan Asap (B/C = 0,67)
Berdasarkan beberapa hasil analisis di atas, tampak bahwa susu kerbau rawa memiliki variasi produk turunan terbanyak dengan nilai B/C yang lebih besar dibandingkan dengan komoditi ramah gambut lainnya.
1.2. Permasalahan
Pelaksanaan ketiga kegiatan tahun 2017 memerlukan tindak lanjut agar sasaran ketiga kegiatan tersebut dapat dicapai dalam rangka restorasi ekosistem gambut di wilayah riset dan Pilot Project. Kajian lanjutan terhadap ketiga kegiatan tersebut diperlukan untuk menjawab 3 permasalahan sebagai berikut:
(1) Bagaimana kondisi lapangan saat ini dalam rangka mencapai tujuan restorasi, baik yang terkait dengan kondisi lahan gambut (sarana yang sudah dibangun, muka air tanah, dan lain-lain) maupun yang terkait dengan kondisi pertanaman (pertumbuhan, gangguan hama dan penyakit tanaman, dan lain-lain).
(2) Apakah pengembangan yang diperlukan di lokasi Pilot Project untuk mencapai target yang telah ditetapkan, baik yang terkait dengan kondisi lahan gambut dan kondisi pertanaman, maupun dalam rangka pengembangan komoditas lokal ramah gambut.
(3) Sejauhmana kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dari sisi finansial (profitabilitas) dan keekonomian.
1.3. Tujuan
Berdasarkan ketiga permasalahan yang dikemukakan di atas, kajian lanjutan ini bertujuan sebagai berikut:
(1) Mendeskripsikan kondisi lapangan saat ini dalam rangka mencapai tujuan restorasi, baik yang terkait dengan kondisi lahan gambut (sarana yang sudah dibangun, muka air tanah, dan lain-lain) maupun yang terkait dengan kondisi pertanaman (pertumbuhan, gangguan hama dan penyakit tanaman, dan lain-lain).
(2) Mengkaji kebutuhan dan melaksanakan pengembangan yang diperlukan di lokasi Pilot Project untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya mengganti tanaman yang mati, menanam tanaman sela dan mengembangkan komoditas lokal ramah gambut.
(3) Mengevaluasi manfaat kegiatan terhadap masyarakat dari sisi finansial (profitabilitas) dan keekonomian.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 4
1.4. Luaran
Sesuai dengan tujuan di atas, maka luaran yang diharapkan dari kajian ini adalah sebagai berikut:
(1) Kondisi lapangan saat ini dan pencapaiannya terhadap tujuan restorasi, baik dari kondisi lahan gambut maupun dari kondisi pertanaman.
(2) Tercapainya target penanaman dan keberlanjutan pertumbuhan tanaman pada lokasi Pilot Project sehingga dapat menjadi contoh lokasi restorasi dan berkembangnya tanaman lokal ramah gambut pada lokasi pengembangan.
(3) Diperolehnya berbagai indikator finansial dan keekonomian pengembangan pilot proyek restorasi gambut terintegrasi dan paludikultur, serta pengembangan komoditas lokal ramah gambut (kerbau).
1.5. Kerangka Kerja Logis
Untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan berdasarkan intervensi yang dilakukan, maka disusun kerangka kerja logis sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Kerangka kerja logis kajian profitabilitas dan keekonomian komoditas ramah gambut
Tujuan 1: Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Pilot Project Restorasi Terintegrasi dan Paludikultur pasca pelaksanaan tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Metode Pembuktian Asumsi
1. Terpantaunya perkembangan kegiatan Pilot Project Restorasi Terintegrasi pasca pelaksanaan tahun 2017
2. Terpantaunya perkembangan kegiatan Pilot Project Paludikultur-Agroforestry pasca pelaksanaan tahun 2017
1. Peningkatan Muka Air Tanah
2. Pertumbuhan Tanaman Paludikultur- Agroforestry serta Restorasi Integrasi
1. Observasi lapangan 2. Pengukuran 3. Wawancara/FGD
1. Tidak ada persoalan atas tanah yang dikelola
2. Program Restorasi telah diterima masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan
Manfaat: Diketahuinya perkembangan kegiatan Pilot Project Restorasi Terintegrasi dan Paludikultur-Agroforestry pasca pelaksanaan tahun 2017 Luaran: Terpetakannya tingkat keberhasilan kegiatan perkembangan kegiatan Pilot Project Restorasi Terintegrasi dan Paludikultur-Agroforestry pasca pelaksanaan tahun 2017 Kegiatan: 1. Aplikasi Lapangan 2. Desk study (penelusuran program, kegiatan, laporan, dll.) 3. Observasi lapangan 4. Wawancara
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 5
5. Focus Group Discussion (FGD)
Tujuan 2: Pengembangan lanjutan kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan (3) Riset Komoditi Lokal Potensial pasca pelaksanaan tahun 2017 dalam bentuk (1) Aktifitas Tehnis dan (2) Aktititas ekonomi-sosial
Sasaran Indikator Kinerja Metode Pembukti Asumsi 1. Peningkatan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam dan ekosistem
2. Perberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pemanfaatan komoditi ramah gambut (Kerbau rawa)
1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyakarat tentang pengelolaan ekosistem gambut
2. Pelatihan kepada masyakarat tentang pemanfaatan komoditi ramah gambut (kerbau rawa)
1. Penyuluhan, sosialiasai dan pelatihan,
2. Observasi lapangan 3. Wawancara 4. FGD 5. Laporan program
dan kegiatan
1. Masyarakat siap berpartisipasi dalam restorasi gambut
2. Terdapat peningkatan partisipasi kerja wanita
Manfaat: Keberlanjutan kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan (3) Riset Komoditi Lokal Potensial pasca pelaksanaan tahun 2017 Luaran: 1. Model Percontohan Restorasi Terintegrasi , Paludikultur-Agroforestry, dan Komoditi Ramah
Gambut 2. Terbentuknya Usaha ekonomi dengan bahan baku komoditi ramah gambut (kerbau rawa) Kegiatan: 1. Desk study (penelusuran program, kegiatan, laporan, dll.) 2. Penyuluhan, pendidikan dan latihan 3. Observasi lapangan 4. Wawancara 5. Focus Group Discussion (FGD)
Tujuan 3: Mengevaluasi perkembangan kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan (3) Riset Komoditi Lokal Potensial pasca pelaksanaan tahun 2017 dari sisi nilai profitabilitas, keekonomian, dan valuasi ekonomi
Sasaran Indikator Kinerja Metode Pembukti
Asumsi
1. Diperolehnya indikator finansial dan keekonomian model kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, dan (2) Pilot Project Paludikultur-
1. Nilai finansial dan ekonomi kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, dan (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan
2. Nilai finansial dan Ekonomi Komoditi Lokal Potensial lahan gambut
1. Observasi lapangan
2. Wawancara 3. FGD 4. Analisis
Profitabilitas dan Keekonomian
5. Laporan
1. Masyarakat konsisten menjaga dan melestarikan kawasan yang telah dibangun.
2. Perhitungan nilai ekonomi lingkungan menggunakan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 6
Agroforestry, 2. Diperolehnya nilai
finansial dan Ekonomi Komoditi Lokal Potensial lahan gambut (kerbau)
(kerbau) Nilai profitabilitas pengolahan susu kerbau rawa berupa nilai Biaya, Penerimaan, Keuntungan, IRR, NPV, B/C
program dan kegiatan
konsep valuasi ekonomi dengan aplikasi harga bayangan.
Manfaat: Mempertahankan kondisi alami gambut dengan tetap dapat memproduksi biomassa dan melestarikan jasa ekosistem pada kondisi lahan gambut basah atau dibasahi kembali Luaran: Nilai profitabilitas, nilai ekonomi dan nilai ekonomi lingkungan dari model (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, dan (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan (3) Komoditi Lokal Potensial lahan gambut dengan memanfaatkan jenis-jenis tanaman ramah gambut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan cepat tumbuh di lahan gambut Kegiatan: 1. Desk study (penelusuran program, kegiatan, laporan, dll.) 2. Observasi lapangan 3. Wawancara 4. Focus Group Discussion (FGD)
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 7
II. KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Kawasan, Ekologi dan Sebaran KHG
Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama. Akumulasi itu terjadi karena lambatnya dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik. Alih penggunaan lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan dan hutan produksi dapat mengancam kelangsungan hidup hutan rawa gambut alami. Kerusakan hutan rawa gambut juga dapat diakibatkan oleh sistem drainase yang dibangun kurang terkendali, sehingga mengakibatkan subsidens dan keringnya lahan gambut yang bersifat tidak dapat kembali seperti kondisi semula (irreversible). Tekanan terhadap lahan gambut dikhawatirkan sedang berlangsung di Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat kerusakan yang makin tinggi (Ananto dan Pasandaran, 2017).
Lahan gambut merupakan lahan suboptimal yang memiliki kesuburan rendah, tingkat kemasaman yang tinggi, dan drainase yang buruk. Ciri utama lahan gambut adalah kandungan karbon minimal 18%, dan ketebalan bahan organik minimal 50 cm (Nurida, et al., 2011; Sabiham dan Sukarman, 2012). Menurut Masganti dan Yuliani (2006) gambut berperan penting dalam kelangsungan ekosistem, mengontrol fungsi-fungsi lingkungan dan biologis yang sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan.
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan seluas 87.017 km2, sebahagian merupakan lahan rawa yang tersebar di daerah bagian timur, mulai dari kabupaten Musirawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, sampai Banyuasin. Lahan rawa yang berpotensi untuk pertanian di Provinsi Sumatera Selatan ada 1.602.490 ha, terdiri atas lahan rawa pasang surut 961.000 ha dan rawa non pasang surut atau lebak 641.490 ha (Direktorat Jendral Pengairan, 1998). Sebagian besar lahan rawa tersebut atau sekitar 1,42 juta ha merupakan lahan rawa gambut (Zulfikar, 2006). Saat ini, hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia di Indonesia (Lubis, 2006).
Beberapa hal yang berhubungan dengan karakteristik dan peran ekologis hutan rawa gambut yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan strategis pengelolaan hutan rawa gambut adalah sebagai berikut (Zulfikar, 2006):
1. Hutan rawa gambut merupakan formasi hutan hujan tropika basah yang mempunyai tingkat kelembaban sangat tinggi, merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap gangguan luar dan susah terpulihkan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Sistem silvikultur dengan mengandalkan suksesi hutan alam lebih menunjukkan keberhasilan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 8
2. Lahan gambut yang kering mempunyai sifat kering tak balik dan sangat mudah terbakar. Kebakaran gambut di bawah permukaan tanah akan sangat sulit dipadamkan dan dapat merusak struktur gambut, menurunkan tingkat permeabilitas pada lapisan permukaan dan dapat menyebabkan lahan gambut menjadi memadat dan menurunkan tinggi permukaan lahan kubah gambut.
3. Gambut mempunyai peran sangat besar dalam menyimpan karbon; pengeringan dan pelepasan ikatan karbon ke udara apabila terjadi kebakaran.
4. Ada dua bentukan sistem lahan lahan rawa, yaitu: alluvial marine dengan tekstur tanah mineral dengan lapisan gambut yang tipis, dan rawa belakang yang membentuk kubah gambut dengan kedalaman gambut yang lebih tebal.
5. Kanalisasi dapat menimbulkan risiko kekeringan kalau tidak diimbangi dengan pengendalian tata air yang baik dan benar.
6. Rehabilitasi pada kawasan hutan rawa gambut sudah terlanjur rusak parah sangat sulit dan mahal, sehingga dananya tidak mungkin disediakan hanya dari anggaran pemerintah atau partisipasi/swadaya masyarakat.
Hasil inventarisasi dan pemetaan Peta Satuan Lahan dan Tanah Provinsi Sumatera Selatan skala 1:250.000 tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Puslit Tanah dan Agroklimat yang telah diperdetail melalui Survei Inventarisasi Lahan Gambut bekerjasama dengan Wetland International tahun 2002. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai ketebalan mulai dari Sangat Dangkal (<50 cm) sampai Dalam (200-400 cm), dan tidak terdapat ketebalan gambut Sangat Dalam lebih dari 400 cm. Kawasan hutan produksi yang didominasi dengan lahan rawa gambut adalah Kelompok Hutan Produksi (HP) Simpang Heran Beyuku, HP Mesuji dan HP Pedamaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas kira-kira 617.350 ha, dan Kelompok Hutan Produksi Sungai Lalan dan Mangsang - Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin dengan luas ± 331.304 ha (Ananto dan Pasandaran, 2017). Sebaran, ketebalan dan luas lahan gambut di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Informasi sebaran lahan gambut Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 terlihat bahwa lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ketebalan sedang (100 - 200 cm) tercatat seluas 547.112 ha dan tersebar di wilayah Pedamaran dan Tulung Selapan (40%), sebagian besar telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman. Lahan gambut di wilayah Mesuji di sekitar desa Gajah Mati (15%) dan yang di dalam kawasan HP Simpang Heran Beyuku (45 %) telah dikonversi dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Lahan gambut dengan ketebalan sedang (100–200 cm) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin terkonsentrasi di daerah sisi sebelah utara Sungai Lalan, mulai dari Karang Agung Timur hingga Bayung Lincir dan menyebar ke Utara – Timur hingga berbatasan dengan hutan mangrove di Taman Nasional Sembilang (Zulfikar, 2006).
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 9
Tabel 2.1. Sebaran dan Luas Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan Tahun1990 dan Tahun 2002
No Kedalaman/Ketebalan
(cm)
Total Luas (ha) Tambahan Luas
(ha) Tahun 1990 Tahun 2002
1 Sangat Dangkal <50 159.036 159.036
2 Dangkal (50-100) 66.200 304.330 238.130
3 Sedang (100-200) 1.308.832 934.045 -374.787
4 Dalam (200-400) 45.009 22.631 -22.378
Jumlah 1..420.042 1.420.042
Sumber :
1. Peta Satuan Lahan dan Tanah skala 1:250.000, Pusat penelitian dan Agroklimat, Bogor, 1990 2. Wetland International dengan sumber dana dari Pemerintah Kanada melalui Canadian International
Development (CIDA) 3. Diaposir STAR I SAR Skala 1:250.000, 1989 4. Landsat MSS, 1990 5. Landsat ETM, 2002
Sebaran lahan gambut dengan kedalaman atau ketebalan 200 – 400 cm hanya ditemukan di daerah sisi barat dan timur dari muara Sungai Lematang – Sungai Musi di Kabupaten Muara Enim dan sebagian kecil di Gelumbang yang masuk wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diperkirakan sangat berperan sebagai areal retensi ketika terjadi luapan sungai Musi dari Sungai Lematang. Lahan gambut di wilayah tersebut masih ditutupi dengan vegetasi hutan gelam dan semak-belukar dan seluruh areal tersebut sedang dalam proses konversi menjadi perkebunan kelapa sawit (Ananto dan Pasandaran, 2017). 2.1.2. Komoditi Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)
Pemilihan Komoditas dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya tanaman pertanian di lahan gambut. Melalui penataan lahan, pada kawasan hutan produksi dapat dibudidayakan berbagai komoditas seperti padi, jeruk, sayuran, dan kelapa sawit. Komoditas hortikultura (sayuran dan buah-buahan) memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada tanaman pangan, tetapi memerlukan teknik budidaya yang lebih rumit. Selain itu, pemilihan komoditas juga harus mempertimbangkan iklim setempat. Pemilihan komoditas tidak hanya terbatas pada tanaman, tetapi juga menyangkut ternak (Masganti, et al. 2011).
Komoditas tanaman yang ditanam di lahan gambut sebaiknya yang adaptif terhadap tanah gambut. Hal itu penting untuk mengurang input sarana produksi yang dibutuhkan sehingga terjadi efisiensi biaya. Ada dua pendekatan dalam mengusahakan tanaman di lahan gambut menurut Sabiham (2006), yaitu:
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 10
1. Pendekatan pada kondisi drainase alami. Pada kondisi drainase alami tanaman yang adaftif adalah padi jenis lokal, dan sagu dari spesies rawa gambut yaitu Metroxylon sago
2. Pendekatan pada kondisi drainase buatan. Pada kondisi drainase buatan ada dua pendekatan yaitu: Kedalaman muka air tanah (40 – 60 cm) tanaman yang baik untuk kondisi seperti ini adalah: padi, sayuran, buah-buahan, dan rumput sebagai pakan ternak. Kedalaman muka air tanah > 60 cm – 100 cm, tanaman yang cocok ialah kelapa sawit, kelapa, dan karet yang diusahakan dalam bentuk perkebunan, dan Accasia crasicarpa yang diusahakan dalam Hutan Tanaman Industri.
Pertimbangan yang perlu diperhatikan petani agar usaha budidaya tanaman hortikultura yang ditanam menguntungkan ialah: pemilihan tanaman atas dasar permintaan pasar, tersedia input bagi usahatani, akses mendapatkan sarana produksi seperti pupuk kandang dan menghemat keberadaan gambut dengan memperlambat dekomposisi gambut melalui pengendalian tinggi muka air tanah (Sagiman, 2005).
Kebutuhan air untuk tanaman tergantung pada jenis tanaman yang diusahakan
atau dibudidayakan pada lahan gambut. Beberapa jenis tanaman dan kebutuhan air yang diperlukan beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan di lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Kebutuhan air untuk pertumbuhan beberapa jenis tanaman di lahan gambut
Tanaman Kebutuhan Air
Tinggi Muka Air opt (m) Periode Maks
Tergenang (Hari)
Pembatas Utama Produktivitas
Min Maks Kelapa sawit 0,60 0,75 3 Kesuburan rendah, daya
jangkar akar rendah, kering
Ubi kayu 0,30 0,60 0 Mekanisasi Sagu 0,30 0,40 0 Tanaman hortikultura
Mekanisasi
Padi 0,10 0,00 Kontrol air dipetakan, hara Nenas 0,75 0,90 1 Mekanisasi Karet 0,75 1,00 Daya jangkar akar rendah Acacia sp. 0,70 0,80 Daya jangkar akar rendah
Sumber: Supriyo et al., 2007
Pembuatan saluran yang terlalu dalam dan lebar akan mempercepat proses drainase dan pada musim kemarau air tanah cukup dalam sehingga menyebabkan tanah menjadi kering. Keadaan ini akan sangat berbahaya untuk tanah gambut karena terjadi penurunan permukaan air tanah secara berlebihan (overdrain) akan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 11
menyebabkan gambut mengering atau mati dan penurunan permukaan tanah gambut (subsidence) terlalu cepat (Suriadikarta, 2012).
Kedalaman permukaan air tanah pada parit kebun diusahakan agar tidak terlalu jauh dari akar tanaman. Jika permukaan air tanah terlalu dalam maka oksidasi berlebih akan mempercepat perombakan gambut, sehingga gambut cepat mengalami subsiden. Acuan kedalaman permukaan air tanah untuk tanaman pertanian lahan gambut menurut Maas et al. dalam Andriesse (1988) dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Kedalaman permukaan air tanah dan ketebalan bahan organik sebagai pembatas produksi tanaman pertanian
Tanaman Kedalaman permukaan air
tanah (cm) Ketebalan bahan
organik (cm) Padi sawah Dekat permukaan <100 Padi ladang Dekat permukaan <100 Jagung 60 – 100 <100 Sorgum 60 – 100 <100 Sayur-sayuran 30 – 60 Bukan pembatas Cabe 30 – 60 Bukan pembatas Kedelai 30 – 60 Bukan pembatas Jahe 60 – 100 Bukan pembatas Kacang Tanah 60 – 100 Bukan pembatas Ubi Jalar 60 – 100 Bukan pembatas Ketela pohon 60 – 100 Bukan pembatas Pisang 60 – 100 <100 Tebu 60 – 100 Bukan pembatas Nanas 60 – 100 Bukan pembatas Cocoa 60 – 100 Bukan pembatas Kelapa sawit 60 – 100 Bukan pembatas Kopi 60 – 100 Bukan pembatas Durian 60 – 100 <100 Rambutan 60 – 100 <200 Kelapa 60 – 100 <100 Jambu Mente 60 – 100 Bukan pembatas Sagu Bukan pembatas Bukan pembatas Karet 60 -100 <200
Sumber: Maas et al. dalam Andriesse, 1988.
2.1.3. Profitabilitas dan Keekonomian
Menurut Wykstra (1971) dalam Sujono (2014), ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang cara-cara alternatif manusia dalam memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenugi keinginan. Atau dengan kata lain, ekonomi mengakui realitas kelangkaan, lalu memikirkan cara mengorganisir masyarakat dalam suatu cara yang menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang paling efisien dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan dimasa depan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 12
Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau suatu kegiatan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu tahun. Sedangkan menurut Giman (2009), profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset kegiatan baik lancar maupun tetap dalam aktifitas produksi.
Penerimaan dan pendapatan usaha memiliki arti yang berbeda. Pendapatan memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian pendapatan tersebut. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilan bunga, royalti dan dividen. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang dijual, dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkannya. Pendapatan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan (Soekartawi, 2002).
Menurut Soekartawi di dalam Psikiatri (2015), pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha. Ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pendapatan antara lain:
1. Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar.
2. Pendapatan bersih adalah penerimaan yang dikurangi dengan total biaya produksi atau penerimaan di kurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap.
3. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan produksi.
Menurut Rahim et al (2007), penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :
TR = total penerimaan Y = produksi yang diperoleh dari suatu usahatani Py = harga produksi
Pendapatan merupakan selisih penerimaan dengan semua biaya produksi. Pendapatan meliputi pendapatan kotor (penerimaan total) dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 13
Pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :
*( ) +
Keterangan:
π = pendapatan (Rp) TR = total penerimaan (Rp) TC = total biaya (Rp) Y = jumlah produksi Py = harga satuan produksi (Rp) Xi = faktor produksi Pxi = harga faktor produksi (Rp) BTT = biaya tetap total (Rp)
Definisi pendapatan menurut Soekartawi (2002), pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Dua tujuan utama analisis pendapatan yaitu menggambarkan keadaan sekarang dari suatu kegiatan usaha, dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari suatu kegiatan usaha. Sedangkan menurut Sumarwan pendapatan diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Pendapatan sebagai balas saja dan kerja sama faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan.
Menurut Soekartawi (2002) di dalam Suratiyah (2009), faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya pendapatan sangat kompleks, namun demikian faktor tersebut dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang akan mempengaruhi pendapatan dan juga biaya adalah antara lain umur petani, pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, jumlah tenaga kerja, luas lahan, dan modal, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah ketersediaan dan harga input, permintaan dan harga jual. Analisis pendapatan usahatani memerlukan dua komponen pokok yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam melihat pendapatan usahatani, antara lain sebagai berikut: a. Pendapatan tunai (farm net cash flow)
Kemampuan usahatani untuk menghasilkan uang tunai dapat diukur oleh adanya pendapatan tunai usahatani. Pendapatan tunai usahatani merupakan selisih antara penerimaan tunai usahatani dengan pengeluaran usahatani. Perhitungan pendapatan usahatani menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan usahatani dan berguna untuk keperluan rumah tangga. b. Pendapatan kotor (gross farm income)
Pendapatan kotor usahatani atau penerimaan kotor (gross return) merupakan ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Pendapatan kotor usahatani juga merupakan nilai produksi (valueof production) total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. Pendapatan kotor usahatani dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan kotor tunai dan pendapatan kotor tidak tunai. Pendapatan kotor tunai didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani yang tidak mencakup pinjaman uang
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 14
untuk keperluan usahatani yang berbentuk benda dan yang dikonsumsi. Sedangkan pendapatan kotor tidak tunai merupakan pendapatan bukan dalam bentuk uang, seperti hasil panen yang dikonsumsi atau pembayaran yang dilakukan dalam bentuk benda. c. Pendapatan bersih (net farm income)
Pendapatan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran total usahatani. Pendapatan bersih usahatani ini mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi atau pendapatan bersih usahatani ini merupakan ukuran keuntungan usahatani yang dapat digunakan untuk menilai dan membandingkan beberapa usahatani lainnya, maka ukuran yang digunakan untuk menilai usahatani ialah dengan penghasilan bersih usahatani yang merupakan pengurangan antara pendapatan bersih usahatani dengan bunga pinjaman, biaya yang diperhitungkan dan penyusutan.
Analisis kelayakan usaha selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar. Dengan melakukan berbagai macam simulasi tersebut, akan diketahui besarnya faktor-faktor resiko yang akan dihadapi, dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu rencana investasi. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan adalah :
1. Metode Non-Discounted Cash Flow Non-Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan
melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang (time value of money). Metode yang dipergunakan adalah Pay Back Period (PBP) Method, dengan formula umum sbb:
Metode PBP merupakan alat ukur yang sangat sederhana, mudah dimengerti dan berfungsi sebagai tahapan paling awal bagi penilaian suatu investasi. Model ini umum digunakan untuk pemilihan alter-natif-alternatif usaha yang mempunyai resiko tinggi, karena modal yang telah ditanamkan harus segera dapat diterima kembali secepat mungkin. Kelemahan utama dari metode PBP ini adalah:
Tidak dapat menganalisa penghasilan usaha setelah modal kembali. Tidak mempertimbangkan nilai waktu uang
2. Metode Discounted Cash Flow
Discounted Cash Flow adalah metode pengukuran investasi dengan melihat nilai waktu uang (time value of money) dalam menghitung tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 15
a. Net Present Value (NPV) NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang
(present value) dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Dengan demikian, NPV dapat dirumuskan:
NPV = PV of Benefit – PV of Capital Cost atau karena PV = (C / (1+i)n), maka:
∑
( ) ∑
( )
dimana: i = bunga tiap periode N = periode (tahun, bulan) - C = modal (capital) C = hasil bersih (proceed) Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian NPV adalah sbb:
1). Jika NPV = 0 (nol), maka hasil investasi (return) usaha akan sama dengan tingkat bunga yang dipakai dalam analisis, atau dengan kata lain usaha tidak untung maupun rugi (impas).
2). Jika NPV = – (negatif), maka investasi tersebut rugi atau hasilnya (return) di bawah tingkat bunga yang dipakai.
3). Jika NPV = + (positif), maka investasi tersebut mengun-tungkan atau hasilnya (return) melebihi tingkat bunga yang dipakai.
Kelemahan utama dari metode NPV ini adalah bahwa ia tidak menganalisis pemilihan alternatif usaha-usaha dengan jumlah investasi yang berbeda.
b. Profitability Index (PI)
Metode analisa PI sangat mirip dengan analisa NPV, karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang (present value). Perbedaannya adalah bahwa satuan yang dipakai dalam NPV adalah nilai uang, sedangkan dalam PI adalah indeks. Rumus perhitungan PI adalah sebagai berikut:
Kriteria penilaian investasi dengan menggunakan PI juga mirip dengan NPV, yaitu sebagai berikut:
- Jika PI > 1, maka investasi dikatakan layak - Jika PI < 1, maka investasi dikatakan tidak layak - Jika PI = 1, maka investasi dikatakan BEP
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 16
c. Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang (present value) dari investasi de-ngan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku, atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri. Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks, karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola try and error. Namun demikian, untuk skenario dua nilai NPV yang telah diketahui sebelumnya, IRR dapat dirumuskan sebagai:
( ) |
( ) |
di mana: NPV1 harus di atas 0 (NPV1 > 0) NPV2 harus di bawah 0 (NPV2 < 0)
3. Analisa Keuntungan
Analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan (pene-tapan keuntungan) dengan menyesuaikan atau set-up harga dan volu-me penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbang-kan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu.
a. Break Even Point (BEP)
Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan/produksi. Analisa yang juga dikenal dengan isti-lah CPV (Cost-Profit-Volume) ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian.
Dalam analisa BEP, faktor-faktor biaya dibedakan menjadi:
- Biaya semi variabel, yaitu biaya yang akan ikut berubah jum-lahnya dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara proporsional. Biaya ini sebagian akan dibe-bankan pada pos biaya tetap, dan sebagian lagi akan dibeban-kan pada pos biaya variabel.
- Biaya variabel, adalah biaya yang akan ikut berubah secara pro-porsional dengan perubahan volume penjualan atau produksi.
- Biaya tetap, adalah biaya yang tidak akan ikut berubah dengan perubahan volume penjualan atau produksi.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 17
Analisa BEP dihitung dengan formula sebagai berikut:
atau dapat juga dituliskan sebagai:
|
|
b. Kontribusi Margin
Kontribusi margin adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utama dari pengukuran kontribusi margin ini adalah analisa penentuan keuntungan maksimum atau kerugian mini-mum. Yang pertama perlu diketahui adalah rasio kontribusi margin, yaitu rasio antara biaya variabel dengan hasil penjualan. Lebih jelasnya, dapat dilihat dari rumusan berikut:
|
|
2.1.4. Benefit Cost Analysis
Analisis Biaya Manfaat (Benefit Cost Analysis) dibangun berdasarkan asumsi ekonomi neoklasik, yang dapat digunakan untuk menemukan alokasi paling efisien di antara penggunaan alternatif sumber daya yang langka, menggunakan pasar harga sebagai panduan. Menurut Barton (1994), asumsi dasar yang terkait dengan ekonomi neoklasik, dan di mana CBA dibangun, adalah:
1. Kesejahteraan sosial adalah jumlah kesejahteraan individu. Agregasi kesejahteraan individu tidak asumsi yang kuat dan pasti pasti harus dibuat.
2. Kesejahteraan individu dapat diukur. Ukuran pengukuran adalah unit moneter. Harga pasar sebagai ukuran tidak dapat digunakan secara langsung dalam CBA, tetapi terlebih dahulu dikoreksi.
3. Individu memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan memilih kombinasi barang, jasa dan tabungan yang menghasilkan jumlah total utilitas terbesar yang mungkin diberikan karena keterbatasan pendapatan mereka.
Total kesejahteraan sosial dari konsumsi barang atau jasa setara dengan jumlah dari kesediaan individu untuk membayar (WTP). Jumlah ini termasuk pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang atau jasa, dan surplus konsumen. Utilitas atau manfaat marjinal dari konsumsi setiap unit barang atau jasa diasumsikan menurun, WTP untuk setiap unit berturut-turut juga menurun. Dua hal penting untuk dicatat terkait penilaian barang dan jasa yaitu : (1) menggunakan pasar harga dikalikan dengan konsumsi memberikan perkiraan minimum utilitas penggunaan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 18
barang dan jasa. (2) Surplus konsumen harus dimasukkan untuk menganalisis nilai keseluruhan untuk individu. Surplus konsumen dalam pengertian ini merupakan konsep nilai bersih dari pengeluaran. Orang dapat melihat bahwa barang dan jasa yang tersedia gratis atau tidak berharga memerlukan konsumen besar kelebihan. Ketika mereka hancur, hilangnya utilitas juga besar (Hufschmidt et. Al., 1983).
Dengan asumsi pasar yang bebas dari distorsi dan distribusi pendapatan di masyarakat itu dianggap dapat diterima secara politik, kurva permintaan individu dapat diagregasikan ke kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar ini pada gilirannya akan mencerminkan kesediaan total untuk membayar barang atau jasa yang dimaksud. Kedua asumsi ini kuat. Dalam CBA mereka bisa sebagian dikoreksi melalui penggunaan koefisien untuk pembobotan efisiensi dan efek sosial.
Mendapatkan manfaat dari penggunaan barang atau jasa juga akan memerlukan biaya sosial. Untuk barang dan layanan yang diperdagangkan di pasar yang tidak terdistorsi, harga pasar akan mewakili yang benar biaya kepada masyarakat tidak menggunakan barang atau jasa dalam penggunaan alternatif terbaiknya. Manfaat bersih yang dapat diturunkan dari alternatif terbaik berikutnya disebut Opportunity Cost. Untuk produsen, biaya marjinal meningkat seiring dengan peningkatan output, karena faktor teknologi dan karena input yang masuk ke produksi menjadi semakin langka. Supply pasar yang baik diwakili oleh kurva biaya marjinal yang naik untuk peningkatan tingkat produksi.
Surplus produsen adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh untuk barang dan total biaya produksinya, atau Opportunity Cost di pasar persiangan sempurna. Surplus produsen juga biasa disebut rente ekonomi. Total kesejahteraan sosial adalah jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Kedua produser surplus dan konsumen surplus berada pada maksimum ketika manfaat sosial marjinal adalah tepat sama dengan biaya sosial marginal. Total manfaat sosial bersih akan menjadi yang terbesar dalam hal ini.
Kebijakan yang berbeda akan memerlukan berbagai kombinasi penawaran dan permintaan, tergantung pada berbagai penggunaan sumber daya yang langka. Jika mereka diperdagangkan di pasar, barang dan jasa disediakan oleh satu alternatif penggunaan yang kompatibel dapat diwakili oleh sejumlah kesetimbangan parsial. Kesejahteraan sosial (surplus produsen ditambah surplus konsumen), untuk setiap barang atau layanan kemudian dapat ditambahkan untuk memberikan perkiraan kesejahteraan sosial total kompatibel menggunakan lembur pengetahuan tentang proses alami.
2.1.5. Analisis Extended Cost-Benefit Analysis (ECBA)
Analisis Biaya Manfaat atau Extended Cost-Benefit Analysis (ECBA) merupakan teknik perhitungan nilai ekonomi. Sejak tahun 1970, CBA menjadi salah satu sistem pendukung keputusan dominan dalam penilaian proyek oleh Bank Dunia.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 19
Menurut Boardman (1996), langkah utama dalam penggunaan teknik CBA untuk salah satu proyek dam di Thailand antara lain : (1) mendefinisikan grup referensi, (2) memilih portofolio dari proyek alternative, (3) mengidentifikasi dampak potensial dari proyek, (4) memprediksi dampak kuantitatif dari keberlangsungan proyek, (5) Memonetisasi keseluruhan dampak, (6) Pemotongan Waktu untuk mengetahui nilai sekarang (present value), (7) total : penjumlahan keseluruhan manfaat dan biaya, (8) menunjukkan analisis sesnsitivitas, (9) merekomendasikan alternative dengan nilai kesejahteraan sosial bersih terbesar. Konsep Analisis Biaya Keuntungan atau A cost-benefit analysis (CBA) digambarkan pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Konsep Analisis Biaya Manfaat atau Extended Cost-Benefit Analysis (ECBA)
Dalam hal barang dan jasa lingkungan yang tidak diperdagangkan di pasar apa pun, biaya sosial biaya adalah Opportunity Cost dari manfaat pengguna terdahulu. Dalam analisis manfaat sosial ada asimetri antara biaya dan manfaat. Manfaat yang hilang adalah biaya dan biaya yang dihindari adalah manfaat. Teknik penilaian untuk memperkirakan kurva permintaan untuk barang dan jasa lingkungan yang tidak dipasarkan digunakan untuk menentukan total WTP konsumen. Dengan asumsi, analisis biaya manfaat sosial akan membandingkan perubahan dalam penawaran dan permintaan kurva untuk semua kegunaan, serta perubahan nilai non penggunaan, yang disyaratkan oleh adanya pilihan kebijakan. Dalam teori itu, opsi kebijakan mungkin diwakili oleh sejumlah perilaku pasar. Keseimbangan dan interaksi dinamis antara sistem ekologi dan ekonomi harus dimodelkan secara kuantitatif. Selanjutnya,
Total Nilai Ekonomi
Keberadaan dan Nilai Warisan :
- Keanekaragaman Hayati
Nilai Non- Guna Nilai Guna
Penggunaan Tak Langsung :
- Penyerapan Karbon
- Konservasi air dan tanah
- Nutrisi Tanah
Nilai Pilihan :
- Ketersediaan air
- Pariwisata - Ekowisata - Produksi
Pertanian
Penggunaan Langsung :
- Buah dan Herbal
- Kayu - HHBK - Margasatwa - Perikanan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 20
sejumlah manfaat lingkungan yang dianggap nyata yang akan dinilai inilah yang dimasukkan dalam perhitungan ECBA.
Dari pembahasan di atas kita memahami bahwa analisis ekonomi atas biaya-manfaat masyarakat didasarkan pada efek kesejahteraan yang diukur dengan kemauan membayar, dan biaya sebesar Opportunity Cost dari sumber daya hilang. Fokusnya adalah pada harga lingkungan, dampak lainnya dari kebijakan atau penggunaan sumber daya masyarakat secara keseluruhan. Perhitungan akuntansi semalama ini hanya menghitung manfaat langsung dan biaya penggunaan sumber daya. Sebuah analisa ekonomi harus mencakup manfaat perbaikan eksternall lingkungan dan biaya kerusakan, serta biaya perlindungan lingkungan untuk masyarakat tindakan, seperti disajikan dalam rumus:
NPV = Bd + Be - Cd – Ce
di mana NPV = nilai sekarang dari penggunaan sumber daya alternatif, Bd = manfaat langsung, Be = manfaat eksternal atau lingkungan, Cd = biaya langsung, dan Ce = biaya lingkungan (Pearce dan Turner, 1990).
Langkah selanjutnya dari ECBA adalah untuk membandingkan biaya dan manfaat. Seperti analisis CBA, perhitungan nilai sekarang dari biaya dan manfaat tetap menjadi perhatian. Isu-isu penting dari ECBA adalah:
1. Dampak keuangan dan ekonomi Dampak keuangan dan ekonomi dari efisiensi ekonomi mungkin yang paling
penting kepada masyarakat lokal dipengaruhi oleh pengembangan sumber daya. Pembuat kebijakan, dan terutama para pemangku kepentingan lokal, akan lebih peduli dengan pengukuran dampak seperti penjualan, pendapatan, pekerjaan, pendapatan pajak, dan neraca pembayaran, dibandingkan dengan langkah-langkah efisiensi ekonomi yang digunakan dalam ECBA. Dalam banyak kasus, koneksi dapat dibuat antara dampak keuangan dari berbagai kegiatan di satu sisi dan sumber daya alternative efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi di sisi lain. Namun, mereka tidak selalu mungkin bergerak ke arah yang sama.
2. Agregasi dan inkrementalisme CBA telah dikritik antara lain karena tingkat informasi agregat yang
berlebihan terhadap kepentingan pembuat keputusan. Satu bahaya dari reduksionisme moneter ini terkait inkrementalisme dalam evaluasi penggunaan sumber daya (Dixon dan Hodgson, 1988).
Kritik terkait lainnya mengacu pada pengujian dimensi kesejahteraan dari CBA konvensional dengan sifatnya yang tertutup dan tidak demokratis. Analisis biaya-manfaat konvensional dapat dibenarkan selama ada konsensus di masyarakat tentang aturan evaluasi yang melekat dalam analisis biaya-manfaat. Ini mengacu pada asumsi neoklasik. Tingkat agregasi yang tinggi dapat berarti bahwa kriteria
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 21
pengambilan keputusan dari ECBA adalah sulit untuk dijelaskan kepada pengguna sumber daya lokal. Kritik ini juga bersifat kolektif di Indonesia bahwa ECBA diletakkan pada fondasi neoklasik preferensi individu sementara preferensi masyarakat secara keseluruhan diabaikan.
3. Ketidaklengkapan Data Satu kritik terhadap ECBA adalah bahwa ECBA seringkali didasarkan pada
ketidaktersediaan data nasional yang tidak lengkap. Beberapa orang meragukan keuntungan dari penggunaan metode tersebut dibandingkan dengan biaya pengumpulan data. Meningkatnya jumlah ECBA studi yang dilakukan yang mencakup efek lingkungan juga merupakan indikasi bahwa keuntungan telah terlihat lebih besar daripada yang selama ini dilakukan, juga di negara-negara berkembang.
4. Monetisasi dan barang-barang yang tidak terukur Masalah-masalah dasar pengukuran ada di mana; (A) pasar sebenarnya jauh
dari sempurna, (b) konsekuensi gangguan lingkungan bersifat heterogen dan tidak bisa diukur secara kuantitatif, dan (c) manfaat yang diperoleh dari kontrol lingkungan adalah heterogen dan tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan yang lain atau dengan pengeluaran untuk kontrol. Mengenai keraguan pengukuran dan perbandingan efek lingkungan yang berbeda, kritik ini membahas asumsi neoklasik individu preferensi yang terukur oleh konsep kesediaan untuk membayar.
Schleyer dan Tomalin (2000), dan Zakai and Chadwick-Furman (2002) dapat digunakan untuk mengukur dampak lingkungan. CBA juga menghadapi masalah data dan pengukuran. Dampak yang tidak terkuantifikasi dari nilai penting bagi masyarakat yang terkena dampak telah ditinggalkan dari analisis biaya-manfaat terakhir untuk alasan yang jelas. Namun, masalah muncul ketika nilai-nilai sosial yang penting ini tidak diperhitungkan oleh pembuat keputusan. Hasil ECBA yang dilengkapi dengan teknik penilaian lain dan analisis ekologi, bisa mengurangi beberapa masalah ini.
Meskipun demikian, diakui bahwa penerapan metode penilaian CBA meninggalkan banyak aspek nilai ekosistem yang tidak terkuantifikasi. Dengan beberapa pengecualian, nilai-nilai tertentu tidak dapat dikuantifikasi dengan akurasi apa pun. Padahal sebenernya, beberapa nilai budaya, sejarah, dan estetika dapat diukur dalam uang istilah dengan metode langsung penilaian kontingen. Masalah lainnya misalnya, ditemukannya kesediaan orang untuk membayar dalam rangka melindungi situs penting budaya (Dixon dan Hodgson, 1988).
Metode penilaian ECBA telah melalui perjalanan panjang selama dua puluh tahun terakhir dalam menyediakan setidaknya perkiraan kasar dari apa yang sebelumnya dianggap tidak dapat dikuantifikasi. Tugas penting dari ECBA, bagaimanapun, harus menyatakan secara eksplisit semua asumsi dan keterbatasan analisis untuk pembuat keputusan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 22
5. Distorsi pasar dan distribusi biaya dan manfaat sosial Sebagaimana telah kita lihat, analisis keuangan menggunakan harga pasar
domestik secara langsung mempengaruhi biaya dan pendapatan pengambil keputusan individu. Namun, dari sudut pandang masyarakat, banyak pasar mengalami distorsi. Distorsi mungkin karena monopoli, intervensi dalam proses pasar melalui pajak dan subsidi, serta ekonomi eksternal dan diseconomies yang berasal dari dampak lingkungan yang tidak diperhitungkan dalam transaksi pasar. Untuk menentukan harga sumberdaya dari sudut pandang ekonomi, harga bayangan perlu dihitung dengan benar dalam konteks distorsi. Harga bayangan ini juga disebut efisiensi harga (Barton, 1994).
6. Irreversibility, ketidakpastian dan risiko Penggunaan sumber daya dan opsi kebijakan tertentu akan menyebabkan
kerusakan permanen pada lingkungan melalui penghancuran spesies tertentu dan habitatnya.
Berdasarkan konsep profitabilitas dan keekonomian di atas, maka upaya untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari kerbau rawa untuk memperoleh manfaat bagi masyarakat perlu dikaji profitabilitas dan keekonomiannya, baik dari perspektif pengusahanya maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kajian profitabilitas dan keekonomian susu kerbau rawa di KHG S.Sebumbung - S.Batok diintisarikan pada Gambar 2.2.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 23
2.2. Kerangka Pemikiran
Pemecahan permasalahan kajian ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada kerangka pemikiran yang secara diagramatis ditampilkan pada Gambar 2.2.
RISET & PILOT PROJECT 2017
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Kajian
Riset Komoditas
Lokal Potensial
Pilot Project Paludikultur
Pilot Project Restorasi Terintegrasi
KEGIATAN 2018: Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut di KHG S. Saleh - S. Sugihan dan KHG S. Sebumbung - S.Batok Kabupaten Ogan Komering
Ilir
1. Monitoring dan Pemeliharaan
2. Pengembangan 3. Evaluasi
Monitoring (Muka air dan Pertumbuhan
Pemeliharaan dan Penyulaman
Paludikultur
Rest. Terintegrasi
Komoditi Lokal (Kerbau Rawa)
Profitabilitas dan Keekonomian
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 24
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat
Kajian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai November 2018 pada dua KHG dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menjadi target riset yaitu: 1. KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan 2. KHG Sungai Sebumbung-Sungai Batok
Pada KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan terdapat beberapa desa yaitu desa Perigi, Beringin Agung, Gelirang, Argo Mulyo, Jalur Mulya, Timbul Jaya, Muara Padang, Sebokor, KP Permata, Karang Anyar, Nusa Makmur, Air Rumbai, dan Rambai. KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan terletak di kecamatan Muara Sugihan, Muara Padang, Air Kumbang, dan Pangkalan Lampam (Gambar 3.1).
Gambar 3.1. Peta KHG Sungai Saleh dan Sungai Sugihan; Kabupaten Banyuasin dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pada KHG Sungai Sebumbung - Sungai Batok, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Pampangan, Kayu Agung Cengal, Jejawi, Sirah Pulau Padang, Pedamaran, dan Pedamaran Timur. Pada KHG tersebut terdapat beberapa desa yang letaknya jauh dari kawasan gambut dan ada beberapa desa yang letaknya berbatasan dengan kawasan Gambut (Gambar 3.2).
Potensi Komoditi Lokal Potensial KHG Saleh- Sugihan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 25
Gambar 3.3. Peta KHG Sungai Sibumbung-Sungai Batok, Kabupaten Ogan
Komering Ilir Gambar 3.2. Peta KHG Sungai Sebumbung-Sungai Batok, Kabupaten Ogan
Komering Ilir
Kajian Monitoring, Pengembangan, dan Evaluasi model kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, dan (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, akan dilaksanakan pada wilayah sekitar lokasi Pilot Project Paludikultur dan Restorasi Terintegrasi yang terletak dalam wilayah KHG S Saleh-S Sugihan, di Desa Perigi, Kecamatan pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua Pilot Project dilaksanakan pada wilayah seluas 18 ha.
Selanjutnya, Nilai finansial dan Ekonomi Komoditi Lokal Potensial lahan gambut untuk komoditi kerbau dilakukan 2 dua KHG yaitu wilayah KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan, dan KHG Sungai Sibumbung-Sungai Batok, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini berkaitan dengan potensi pengembangan Komoditi Lokal Potensial lahan gambut untuk komoditi kerbau di kedua KHG.
3.2. Metode Pendekatan
Wilayah studi yang diteliti meliputi 2 KHG yang sangat luas di kabupaten Ogan Komering Ilir. Studi tersebut dilaksanakan dengan metode riset aksi. Untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam studi digunakan 3 pendekatan. Pertama pendekatan kesatuan hidrologis gambut (KHG), kedua pendekatan wilayah administratif, dan ketiga pendekatan ruang kegiatan. Untuk
Potensi Komoditi Lokal Potensial Di Khg Sungai
Sibumbung-Sungai Batok
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 26
memudahkan koordinasi dan memaksimalkan informasi dan data yang diperoleh dilakukan pendekatan perwilayah kecamatan dari KHG yang diutamakan.
3.3. Pelaksanaan Kajian
Kegiatan kajian pada tahun 2018 akan dilaksanakan melalui 3 aktivitas, yaitu:
(1) Monitoring:
Kegiatan monitoring akan dilaksanakan pada lokasi kegiatan pilot project tahun 2017, yaitu restorasi gambut terintegrasi dan restorasi gambut berbasis paludikultur di Desa Perigi. Monitoring akan dilaksanakan dua kali, yaitu pada saat awal kegiatan tahun 2018 dilaksanakan dan pada saat menjelang berakhirnya kegiatan tahun 2018. Monitoring pertama dilakukan untuk mengamati perubahan yang terjadi sejak awal kegiatan dilaksanakan (tahun 2017) hingga kondisi saat ini. Aspek yang dimonitor meliputi (a) perubahan muka air tanah di lahan gambut dan fluktuasinya, (b) pertumbuhan tanaman, (c) keadaan infrastruktur yang telah dibangun pada tahun 2017. Monitoring kedua dilakukan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada fase pengembangan yang meliputi (a) pengamatan pertumbuhan tanaman, (b) serangan hama dan penyakit dan pengendaliannya, (c) kebutuhan pemupukan dan lain-lain, (d) lanjutan pengamatan muka air tanah, infrastruktur, operasi dan pemeliharaan infrastruktur.
(2) Pengembangan:
Pengembangan dari kegiatan Pilot Project pada poin (1), yang meliputi (a) penyulaman, (b) penanaman tanaman sela/tanaman semusim, (c) pemeliharaan. Pengembangan tanaman lokal potensial ramah gambut dilaksanakan juga dengan mengidentifikasi tanaman purun di lahan masyarakat yang berada di sekitar lokasi Pilot Project.
(3) Evaluasi profitabilitas dan keekonomian:
Evaluasi akan dilakukan terhadap (a) valuasi ekonomi atas manfaat lingkungan dari Pilot Project dan pengembangan komoditas ramah gambut dilaksanakan pada lokasi Pilot Project dengan mengestimasi nilai lingkungan dari penanaman tanaman sela/tanaman semusim yang hasilnya dapat dimanfaatkan, (b) penilaian profitabilitas dan penilaian keekonomian dilaksanakan untuk pengembangan komoditi ramah gambut (kerbau).
3.4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dan informasi melalui 3 cara, yaitu: 1. Observasi lapangan; 2. Wawancara (terstruktur, mendalam);
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 27
3. Focus Group Discussion (FGD) dan Perberdayaan Masyarakat. 3.4.1. Observasi Lapangan
Observasi atau survei lapangan dilakukan membuat dokumentasi data dan foto-foto lokasi survei. Tahapan Observasi lapangan ialah sebagai berikut:
3.4.1.1 Kunjungan ke kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayu Agung dan 3.4.1.2 Kunjungan ke kecamatan, khususnya desa dan komoditi yang letaknya
berdekatan dengan kawasan KHG. 3.4.1.3 Kunjungan ke desa untuk melakukan survei komoditi:
Nilai finansial dan ekonomi pengembangan model kegiatan (1) Pilot Project Restorasi Terintegrasi, dan (2) Pilot Project Paludikultur-Agroforestry, dan
Nilai finansial dan ekonomi Komoditi Lokal Potensial lahan gambut (kerbau rawa)
3.4.2. Wawancara
Wawancara terstruktur dan mendalam dilaksanakan dengan menggunakan panduan kuisioner yang telah dipersiapkan. 3.4.3. Focus Group Discussion (FGD) dan Pemberdayaan Masyarakat
FGD dapat didefinisikan sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. GD merupakan sebuah proses pengumpulan data dan karenanya mengutamakan proses. FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai konsesus. FGD bertujuan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula. Kecuali apabila masalah atau topik yang didiskusikan tentang pemecahan masalah, maka FGD tentu berguna untuk mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat di lahan gambut, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, tim peneliti berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses Pemberdayaan Masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu keberhasilan pilot project yang telah dibangun pada tahun 2017. Menjalankan pendekatan Perberdayaan Masyarakat dalam menjalankan project berbasis masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ketersediaanya terbatas. Hal ini akan meningkatkan dan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 28
memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab serta merasakan manfaat dari adanya pilot project tersebut.
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh melalui kajian ini diolah dengan menggunakan indikator profitabilitas, antara lain: a) Net Present Value (NPV), b) Internal Rate of Return (IRR), c) Benefit Cost Ratio (BCR), dan d) Payback Period (PP). Analisis profitabilitas secara garis besar dibagi 2 bagian, yaitu analisis finansial menggunakan indikator NPV, BCR, IRR, PP dan analisis sensitivitas untuk melihat hasil analisis kelayakan finansial berdasarkan berbagai kemungkinan yang terjadi.
NPV (Net Present Value)
Parameter ini didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke nilai sekarang untuk mendapatkan nilai netto. Jika nilainya > 0 maka dikatakan proyek tersebut layak, jika < 0 maka dikatakan tidak layak. Adapun perumusan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih (NPV) adalah (Soeharto, 1999):
NPV = ∑
∑
BCR (Benefit Cost Ratio)
Parameter ini didasarkan atas perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika nilainya > 1 maka dikatakan proyek tersebut layak, jika < 1 maka dikatakan tidak layak. Adapun perumusan yang digunakan dapat dilihat pada rumus sebagai berikut (Soeharto, 1999):
BCR =
IRR (Internal Rate of Return)
Internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi suatu rencana investasi agar dapat diterima. Besarnya IRR ini tidak ditentukan secara langsung, melainkan dengan simulasi untuk mendapatkan nilai NPV=0 sebagai prasyaratnya. Adapun perumusan yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut (Soeharto, 1999):
∑
∑
PP (Payback Period)
Periode pengembalian (payback period) adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi. PP dibagi menjadi 2, yaitu Simple Payback Period (tanpa memperhitungkan suku bunga) dan Discounted Payback Period
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 29
(memperhitungkan suku bunga). Adapun rumus payback period dapat dilihat di bawah ini:
∑
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pemeliharaan Kerbau Rawa 4.1.1. Latar Belakang
Luas lahan rawa di Indonesia mencapai 34,93 juta ha atau 18,28% dari luas daratan Indonesia, yang tersebar di Sumatera ±12,93 juta ha, Jawa ±0,90 juta ha, Kalimantan ±10,02 juta ha, Sulawesi ±1,05 juta ha dan Papua ±9,87 juta ha (BBSDLP, 2014). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah Sumatera memiliki lahan rawa paling luas di Indonesia, dimana dari luas tersebut lahan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat baik dalam hal pertanian maupun peternakan. Berdasarkan hasil riset komoditas lokal potensial yang telah dilakukan sebelumnya dibawah kerjasama BRG dan Unsri tahun 2017, ditemukan beberapa komoditi potensial yang berada di lahan gambut wilayah Sumatera khusunya Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya yakni kerbau rawa dengan potensi 2.320 ekor/tahun pada KHG SS dan 2.583 ekor/tahun pada KHG SB. Kecamatan Pampangan (KHG SB) merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi komoditi ramah gambut yang mumpuni.
Kerbau rawa merupakan salah satu asset nasional yang sering dilupakan. Kepemilikan kerbau bagi petani mempunyai jangkauan luas di daerah pedesaan meskipun jumlahnya masih dibawah kepemilikan ternak sapi. Walaupun populasi kerbau menurun dan tidak merata di sebagian besar wilayah Indonesia, kerbau dalam jangka waktu 10 tahun terakhir telah menyumbang rata-rata 44.518 ton daging per tahun setara dengan 2,11% dari produksi daging nasional (Dirjen Peternakan, 2006). Permintaan dan penawaran produksi daging dan susu semakin tidak berimbang sehingga impor semakin membengkak dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016, dari sisi volume, impor peternakan Indonesia mencapai 1,6 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 19,23 persen dibandingkan volume impor tahun 2015 sebesar 1,4 juta ton. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan volume impor hasil ternak sebesar 31, 67 persen (Kementerian Pertanian, 2017). Status kerbau rawa yang hanya menjadi aset usahatani kecil di pedesaan dirasa sangat sia-sia mengingat kerbau memiliki potensi ekonomis untuk dikembangkan, baik dalam hal produksi daging maupun susu yang dapat menjadi bahan dasar perbaikan gizi masyarakat.
Kerbau rawa yang banyak dipelihara oleh masyarakat memang bukan kerbau tipe susu tetapi di beberapa daerah para peternak melakukan pemerahan. Produksi susu dari setiap ternak kerbau yang diperah berkisar antara 1,50 – 2,0 liter/ekor/hari dengan lama pemerahan sekitar 7 bulan (Zulbardi, 2002). Tingginya kadar lemak di dalam susu kerbau, membuat para peternak kerbau memerah susu kerbau dan menjadikannya sebagai produk pascapanen yang spesifik sehingga ditemukanlah dali di Sumatera Utara, Dadih di Sumatera Barat, Gulo Puan di Sumatera Selatan, Dangke di Sulawesi dan susu goreng di NTT dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 31
ternak kerbau rawa perlu mendapat perhatian sehingga tidak lagi berstatus sebagai pelengkap, tetapi menjadi salah satu komoditas yang dapat diandalkan bagi kehidupan masyarakat peternak.
Responden riset terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha pemeliharaan kerbau rawa yang berasal dari beberapa desa terpilih di Kecamatan Pampangan, yakni Desa Pulau Layang, Desa Bangsal, Desa Kuro, Desa Menggeris dan Desa Pampangan. Profil usaha kerbau rawa dianalisis berdasarkan beberapa kriteria yakni asal desa, jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan utama dan sampingan, pendidikan, status kepemilikan lahan dan analisis mengenai usaha ternak kerbau rawa.
4.1.2. Tujuan
Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas pemeliharaan kerbau rawa sebagai salah satu komoditi potensial ramah gambut pada KHG S. Saleh – S. Sugihan dan KHG S. Sebumbung – S. Batok Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4.1.3. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan yang digunakan adalah metode survey. Metode penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, dimana responden atau sampel contoh merupakan masyarakat yang memiliki usaha pemeliharaan kerbau, baik masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak maupun yang berusaha perorangan pada KHG S. Saleh – S. Sugihan dan KHG S. Sebumbung – S. Batok Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4.1.4. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa
Berdasarkan jenis kelamin, semua rumah tangga sampel yang diamati adalah laki-laki (100%), semua rumah tangga sampel beragama Islam. Jika dianalisis berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dimiliki, maka rata-rata jumlah anggota keluarga rumah tangga sampel sebanyak 5 orang. Jumlah masing-masing responden pada tiap Desa dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut.
Tabel 4.1. Jumlah Responden Pemelihara Kerbau Rawa di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
No. Nama Desa Jumlah (orang) 1. Pulau Layang 22 2. Bangsal 10 3. Kuro 15 4. Menggeris 14 5. Pampangan 12
Total 73
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 32
Dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa Desa Pulau Layang memiliki jumlah anggota rumah tangga sampel terbanyak. Hal tersebut dikarenakan Desa Pulau Layang memiliki 2 kelompok ternak kerbau, yakni Kelompok Kencana sebanyak 10 anggota yang diketuai oleh Pak Komri dan Kelompok Gogo Rancah sebanyak 9 anggota yang diketuai oleh Pak Sarkowi, serta 3 masyarakat yang berusaha ternak secara perorangan.
Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok di Desa Pulau Layang terkait usaha pemeliharaan kerbau rawa, yakni lahan pertanian dan lahan pakan kerbau yang tidak pasti batasannya. Sehingga sering terjadi perebutan lahan oleh kedua belah pihak. Biasanya untuk lahan pakan, kedua kelompok memanfaatkan lahan desa yang tersedia dan tidak ditanami padi.
Jika dianalisis berdasarkan usia, rata-rata petani pemelihara kerbau rawa di Desa Pulau Layang berusia 50 tahun dimana angka tersebut menunjukkan bahwa petani pemelihara kerbau rawa tidak berada pada usia produktif untuk melakukan kegiatan usaha. Pendidikan petani contoh juga berada pada rata-rata tingkat pendidikan Sekolah dasar.
Di Desa Pulau Layang, kegiatan pemeliharaan atau usaha kerbau rawa bukan merupakan pekerjaan utama yang dilakukan oleh masyarakat melainkan sebagai pekerjaan sampingan. Sebagian besar masyarakat petani contoh memiliki lahan sawah pribadi dengan rata-rata luas antara 0,25 – 1,0 Ha. Masyarakat Desa Pulau Layang juga banyak yang berusaha karet dimana rata-rata petani contoh hampir seluruhnya (95,5%) memiliki kebun karet pribadi dengan luas antara 0,1 – 0,25 Ha.
Tabel 4.2. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Pulau Layang Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin
1. Laki-laki 22 100 2. Perempuan 0 0
Total Jumlah 22 100 Usia
1. 38 – 45 Tahun 7 31,8 2. 46 – 54 Tahun 8 36,4 3. 55 – 67 Tahun 7 31,8
Total Jumlah 22 100 Jumlah Anggota Keluarga
1. 1– 4 orang 12 54,5 2. 5 – 7 orang 9 41,0 3. >7 orang 1 4,5 Total Jumlah 22 100
Pendidikan 1. SD 11 50
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 33
2. SMP 8 36,4 3. SMA 3 13,6
Total Jumlah 22 100 Pekerjaan Utama
1. Petani 14 63,6 2. Karet 8 36,4
Total Jumlah 22 100 Pekerjaan Sampingan 1
1. Tidak ada 1 4,5 2. Petani 8 36,4 3. Ternak 12 54,5 4. Pedagang 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Pekerjaan Sampingan 2
1. Tidak ada 19 86,5 2. Karet 1 4,5 3. Pedagang 2 9,0
Total Jumlah 22 100 Pekerjaan Sampingan 3
1. Tidak ada 21 95,5 2. Karet 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Lahan Sawah Milik Sendiri
1. 0,25 – 1 Ha 17 77,3 2. 1,1 – 3 Ha 5 22,7
Total Jumlah 22 100 Lahan Sawah Garapan
1. Tidak ada 21 95,5 2. 3 Ha 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Lahan Sawah Sewa
1. Tidak ada 21 95,5 2. 1 Ha 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Ladang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Ladang Garapan
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Ladang Sewa
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Kebun Milik Sendiri
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 34
1. 0,1 – 0,25 Ha 21 95,5 2. 0,26 – 1 Ha 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Kebun Garapan
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Kebun Sewa
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100
Selanjutnya Tabel 4.3. menyajikan profil petani kerbau di Desa Bangsal. Di desa ini terdapat satu kelompok petani kerbau, yakni Kelompok Gembala yang beranggotakan 10 orang dan diketuai oleh Pak Amir. Jika dianalisis berdasarkan usia, rata-rata petani contoh di Desa bangsal berusia 40,5 tahun, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. Di Desa Bangsal pendidikan yang ditempuh oleh petani contoh hanya sampai tingkat Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak lulus/berhenti dari sekolah.
Di Desa Bangsal, kegiatan pemeliharaan atau usaha kerbau rawa sebagian besar (60%) merupakan pekerjaan utama yang dilakukan oleh petani contoh sedangkan sisanya (40%) menjadikan kegiatan pemeliharaan ternak kerbau sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata masyarakat petani contoh memiliki lahan sawah pribadi dengan rata-rata luas 0,255 Ha. Masyarakat Desa Bangsal juga banyak yang berusaha karet dimana rata-rata petani contoh (70%) memiliki kebun karet pribadi dengan luas 0,25 Ha.
Tabel 4.3. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Bangsal Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin
1. Laki-laki 10 100 2. Perempuan 0 0
Total Jumlah 10 100 Usia
1. 34 – 39 Tahun 4 40,0 2. 40 – 49 Tahun 3 30,0 3. 50 – 59 Tahun 3 30,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Anggota Keluarga
1. 1– 4 orang 4 40,0 2. 5 – 6 orang 6 60,0 Total Jumlah 22 100
Pendidikan 1. Tidak Lulus 1 10,0
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 35
2. SD 4 40,0 3. SMP 2 20,0 4. SMA 3 30,0
Total Jumlah 10 100 Pekerjaan Utama
1. Petani 3 30,0 2. Ternak 6 60,0 3. Swasta 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Pekerjaan Sampingan 1
1. Petani 5 50,0 2. Ternak 4 40,0 3. Karet 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Pekerjaan Sampingan 2 1. Tidak ada 7 70,0 2. Karet 3 30,0 Total Jumlah 10 100 Pekerjaan Sampingan 3 1. Tidak ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Sawah Milik Sendiri
1. 0,1 – 25 Ha 5 50,0 2. 0,26 – 1 Ha 5 50,0
Total Jumlah 10 100 Lahan Sawah Garapan
1. Tidak ada 9 90,0 2. 0,1 – 0,25 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Lahan Sawah Sewa
1. Tidak ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Ladang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Ladang Garapan
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Ladang Sewa
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Kebun Milik Sendiri
1. 0,1 – 0,25 Ha 7 70,0 2. 0,26 – 3 Ha 3 30,0
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 36
Total Jumlah 10 100 Kebun Garapan
1. 0,1 – 0,25 10 100 Total Jumlah 10 100 Kebun Sewa
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100
Selanjutnya, Tabel 4.4.menyajikan profil petani pemelihara kerbau rawa di Desa Kuro. Di Desa ini terdapat satu kelompok petani kerbau, yakni Kelompok Karya bersama yang diketuai Oleh Pak M. Awal Gunadi serta 3 anggota masyarakat yang tidak tergabung ke dalam kelompok. Jika dianalisis berdasarkan usia, rata-rata petani contoh di Desa Kuro berusia 45 tahun, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. Di Desa kuro, rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh petani contoh, yakni tingkat SMP.
Berdasarkan tata wilayah, Desa Kuro dan Desa Bangsal termasuk ke dalam satu rumpun dimana batas desa hanya dibatasi oleh masjid. Sedangkan untuk hal yang bersangkutan dengan usaha ternak kerbau seperti kandang, lahan pakan dan lahan gembala tergabung di satu tempat. Di Desa Kuro, kegiatan pemeliharaan atau usaha kerbau rawa sebagian besar (46,7%) merupakan pekerjaan utama yang dilakukan oleh petani contoh sedangkan sisanya (46,7%) menjadikan kegiatan pemeliharaan ternak kerbau sebagai pekerjaan sampingan pertama dan satu orang (6,7%) menjadikan kegiatan pemeliharaan kerbau sebagai pekerjaan sampingan kedua. Rata-rata masyarakat petani contoh memiliki lahan sawah pribadi dengan rata-rata luas 0,5 Ha.
Tabel 4.4. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Kuro Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin
1. Laki-laki 15 100 2. Perempuan 0 0
Total Jumlah 15 100 Usia
1. 34 – 41 Tahun 6 40,0 2. 42 – 48 Tahun 6 40,0 3. 49 – 55 Tahun 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Anggota Keluarga
1. 1– 4 orang 7 46,7 2. 5 – 7 orang 8 53,3 Total Jumlah 15 100
Pendidikan 1. SD 4 26,7
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 37
2. SMP 4 26,7 3. SMA 7 46,7
Total Jumlah 15 100 Pekerjaan Utama
1. Petani 7 46,7 2. Ternak 7 46,7 3. Guru 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Pekerjaan Sampingan 1
1. Petani 7 46,7 2. Ternak 7 46,7 3. Karet 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Pekerjaan Sampingan 2
1. Tidak ada 11 73,3 2. Petani 1 6,7 3. Ternak 1 6,7 4. Karet 2 13,3
Total Jumlah 15 100 Pekerjaan Sampingan 3
1. Tidak ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Lahan Sawah Milik Sendiri
1. 0,5 – 1 Ha 13 86,7 2. 1,1 – 3 Ha 2 13,3
Total Jumlah 15 100 Lahan Sawah Garapan
1. Tidak ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Lahan Sawah Sewa
1. Tidak ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Ladang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Ladang Garapan
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Ladang Sewa
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Kebun Milik Sendiri
1. Tidak Ada 13 86,7 2. 0,1 – 0,5 Ha 1 6,7
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 38
3. 0,26 – 0,75 Ha 1 6,7 Total Jumlah 15 100 Kebun Garapan
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Kebun Sewa
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100
Selanjutnya, Tabel 4.5. menyajikan profil petani Pemelihara kerbau rawa di Desa Menggeris. Di Desa ini terdapat satu kelompok petani kerbau, yakni Kelompok Harapan bersama yang diketuai Oleh Pak H. Kasmir serta 1 anggota masyarakat yang tidak tergabung ke dalam kelompok. Jika dianalisis berdasarkan usia, rata-rata petani contoh di Desa Menggeris berusia 43 tahun, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. Di Desa Menggeris rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh petani contoh, yakni tingkat SD.
Di Desa Menggeris, kegiatan pemeliharaan atau usaha kerbau rawa 42,9% merupakan pekerjaan utama yang dilakukan oleh petani contoh sedangkan sisanya (57,1%) menjadikan kegiatan pemeliharaan ternak kerbau sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata masyarakat petani contoh berusahatani karet dengan luas kebun milik sendiri rata-rata 0,1–1,0 Ha dan memiliki lahan sawah pribadi dengan rata-rata luas 0,1-1,0 Ha.
Tabel 4.5. Profil Petani Pemelihara Kerbau Rawa di Desa Menggeris Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin
1. Laki-laki 14 100 2. Perempuan 0 0
Total Jumlah 14 100 Usia
1. 27 – 39 Tahun 5 35,7 2. 40 – 46 Tahun 5 35,7 3. 47 – 59 Tahun 4 28,6
Total Jumlah 14 100 Jumlah Anggota Keluarga
1. 1– 4 orang 6 42,9 2. 5 – 7 orang 5 35,7 3. >7 orang 3 21,4 Total Jumlah 14 100
Pendidikan 1. Tidak Sekolah 1 7,1 2. SD 6 42,9
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 39
3. SMP 2 14,3 4. SMA 4 28,6 5. Sarjana 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Pekerjaan Utama
1. Petani 2 14,3 2. Ternak 6 42,9 3. Karet 5 35,7 4. PNS 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Pekerjaan Sampingan 1
1. Ternak 8 57,1 2. Karet 6 42,9
Total Jumlah 14 100 Pekerjaan Sampingan 2 1. Tidak ada 12 85,7 2. Karet 1 7,1 3. Pedagang 1 7,1 Total Jumlah 14 100 Pekerjaan Sampingan 3 1. Tidak ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Sawah Milik Sendiri
Tidak Ada 11 78,6 1. 0,7 – 1,0 Ha 2 14,3 2. 1,1 – 1,5 Ha 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Lahan Sawah Garapan
1. Tidak ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Sawah Sewa
1. Tidak ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Ladang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Ladang Garapan
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Ladang Sewa
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Kebun Milik Sendiri
1. Tidak Ada 2 14,3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 40
2. 0,1 – 1,0Ha 10 71,5 3. 1,1 – 1,5 Ha 1 7,1 4. 25 Ha 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Kebun Garapan
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Kebun Sewa
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100
Selanjutnya, Tabel 4.6. menyajikan profil petani Pemelihara kerbau rawa di Desa Pampangan. Di Desa ini terdapat satu kelompok petani kerbau, yakni Kelompok Sumber Harapan yang diketuai Oleh Pak Sulaiman. Jika dianalisis berdasarkan usia, rata-rata petani contoh di Desa Pampangan berusia 42 tahun, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang. Di Desa Pampangan rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh petani contoh, yakni tingkat SMP.
Di Desa Pampangan, kegiatan pemeliharaan atau usaha kerbau rawa hanya dua orang (16,7%) yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Sedangkan sisanya yakni 10 orang (83,3%) menjadikan kegiatan pemeliharaan ternak kerbau sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata masyarakat petani contoh memiliki lahan sawah pribadi dengan rata-rata luas 0,5 Ha.
Tabel 4.6. Profil Petani Pemelihara Ternak Kerbau di Desa Pampangan Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Kelamin
1. Laki-laki 12 100 2. Perempuan 0 0
Total Jumlah 12 100 Usia
1. 35 – 38 Tahun 4 33,3 2. 39 – 43 Tahun 4 33,3 3. 44 – 54 Tahun 4 33,3
Total Jumlah 12 99,9 Jumlah Anggota Keluarga
1. 1– 4 orang 3 25,0 2. 5 – 7 orang 9 75,0 3. >7 orang 0 0 Total Jumlah 12 100
Pendidikan 1. SD 5 41,7 2. SMP 3 25,0 3. SMA 4 33,3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 41
Total Jumlah 12 100 Pekerjaan Utama
1. Petani 7 58,3 2. Ternak 2 16,7 3. Pedagang 1 8,3 4. Swasta 2 16,7
Total Jumlah 12 100 Pekerjaan Sampingan 1
1. Tidak Ada 1 8,3 2. petani 1 8,3 3. Ternak 10 83,3
Total Jumlah 12 100 Pekerjaan Sampingan 2 1. Tidak ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Pekerjaan Sampingan 3 1. Tidak ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Lahan Sawah Milik Sendiri
1. Tidak Ada 4 33,3 2. 0,5 – 1,0 Ha 8 66,7
Total Jumlah 12 100 Lahan Sawah Garapan
1. Tidak ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Lahan Sawah Sewa
1. Tidak ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Ladang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Ladang Garapan
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Ladang Sewa
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Kebun Milik Sendiri
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Kebun Garapan
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Kebun Sewa
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 42
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100
4.1.5. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa
Kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa di Kecamatan Pampangan telah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa tersebut dibagi atas pola individu dan pola kelompok. Pola pemeliharaan tersebut tidak memiliki perbedaan yang besar mengingat sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat peternak di Kecamatan Pampangan tidak jauh berbeda antara pola kelompok dan pola individu. Hal yang membedakan hanyalah ketersedian luas kandang dan lahan pakan. Kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa dapat dilihat pada gambar 4.1. sampai gambar 4. 3 berikut.
Gambar 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok
Gambar 4.2. Kegiatan Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individu
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 43
(a) (b)Gambar 4.3. Pemberian Pakan Konsentrat pada kegiatan pemeliharaan Pola Kelompok
& Kerbau Pola Individu yang mencari makannya sendiri
4.1.5.1. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pulau Layang
Tabel 4.7. menyajikan profil usaha pemeliharaan kerbau rawa di Desa Pulau Layang. Desa ini memiliki dua kelompok, yakni Kelompok Kencana (10 anggota) dan Kelompok Gogo Rancah (9 anggota) dan 3 orang petani contoh yang tidak tergabung dalam kelompok. Rata-rata petani contoh memulai usaha pemeliharaan kerbau rawa pada tahun 1990 dan dirintis bersama oleh keluarga.
Jika dianalisis, jumlah ternak pribadi milik petani contoh rata-rata sebanyak 2 ekor untuk anak kerbau, 1 ekor untuk kerbau muda jantan, 3 ekor untuk kerbau muda betina dan 6 ekor untuk kerbau dewasa betina. Sedangkan untuk kerbau titipan yang diusahakan oleh petani contoh pemelihara kerbau rawa di Desa Pulau Layang, rata-rata tidak memelihara. Hanya ada sebagian kecil yang memelihara kerbau titipan, antara lain dengan kategori kerbau berukuran anak (2 orang), kerbau muda betina (1 orang) dan kerbau dewasa betina (4 orang).
Tabel 4.7. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pulau Layang Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Usaha
1. Perorangan 3 86,4 2. Kelompok 19 13,6
Total Jumlah 22 100 Tahun Mulai Usaha
1. 1975 - 1986 9 40,9 2. 1987 – 2000 9 40,9 3. 2001 – 2018 4 14,2
Total Jumlah 22 100 Siapa yang Merintis Usaha
1. Pribadi 5 22,7 2. Keluarga 17 77,3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 43
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Anak Kerbau
1. Tidak Ada 5 22,7 2. 1 – 3 ekor 12 54,6 3. 4 – 8 ekor 5 22,7
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 17 77,3 2. 2 ekor 5 22,7
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Betina
1. Tidak Ada 18 81,8 2. 1 -2 ekor 4 18,2
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 11 50,0 2. 1 - 3 ekor 6 27,3 3. 5 – 7 ekor 4 18,2 4. 14 ekor 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 7 31,8 2. 1 – 3 ekor 6 27,3 3. 4 – 8 ekor 6 27,3 4. 9 – 18 ekor 3 13,6
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 16 72,7 2. 1 – 2 ekor 6 27,3
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 2 9,1 2. 1 – 3 ekor 7 31,8 3. 4 – 10 ekor 9 40,9 4. 11 – 30 ekor 4 18,2
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Anak Kerbau
1. Tidak Ada 20 90,9 2. 2 – 4 ekor 2 9,1
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau sapihan Betina
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 44
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 21 95,5 2. 5 ekor 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 18 81,9 2. 1 - 3 ekor 3 13,6 3. 9 ekor 1 4,5
Total Jumlah 22 100
Selanjutnya, Tabel 4.8 menyajikan status kepemilikan serta luaskandang, lahan pakan, dan lahan penggembalaan yang dimiliki oleh petani pemelihara kerbau rawa di Desa Pulau Layang.
Tabel 4.8. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Pulau Layang Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Kandang Milik Sendiri
1. 0 – 0,0015 Ha 8 36,4 2. 0,0016 – 0,004 Ha 6 27,2 3. 0,0041 – 0,015 Ha 8 36,4
Total Jumlah 22 100 Kandang Kelompok
1. Tidak Ada 20 90,9 2. 0,0035 – 0,1 Ha 2 9,1
Total Jumlah 22 100 Kandang Komunal
1. Tidak Ada 20 90,9 2. 0,008 – 0,015 Ha 2 9,1
Total Jumlah 22 100 Lahan Pakan Milik Sendiri
1. Tidak Ada 21 95,5 2. 2,5 Ha 1 4,5
Total Jumlah 22 100 Lahan Pakan Kelompok
1. Tidak Ada 22 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 45
Total Jumlah 22 100 Lahan Pakan Komunal
1. Tidak Ada 9 40,9 2. 200 Ha 13 59,1
Total Jumlah 22 100 Lahan Gembala Milik Sendiri
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Lahan Gembala Kelompok
1. Tidak Ada 22 100 Total Jumlah 22 100 Lahan Gembala Komunal
1. Tidak Ada 3 13,6 2. 200 Ha 19 86,4
Total Jumlah 22 100
4.1.5.2. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Bangsal
Tabel 4.9. menyajikan profil usaha pemeliharaan kerbau rawa di Desa Bangsal. Desa ini memiliki satu kelompok, yakni Kelompok Gembala (10 anggota) Rata-rata petani contoh memulai usaha pemeliharaan kerbau rawa pada tahun 1992 dan dirintis bersama oleh keluarga.
Jika dianalisis, jumlah ternak pribadi milik petani contoh rata-rata sebanyak 2 ekor untuk anak kerbau, 2 ekor untuk kerbau muda betina dan 4 ekor untuk kerbau dewasa jantan. Sedangkan untuk kerbau titipan yang diusahakan oleh petani contoh pemelihara kerbau rawa di Desa Bangsal, rata-rata tidak memelihara. Hanya ada sebagian kecil yang memelihara kerbau titipan, antara lain dengan kategori kerbau berukuran anak (4 orang), kerbau muda jantan (3 orang), kerbau muda betina (1 orang), kerbau dewasa jantan (1 orang) dan kerbau dewasa betina (5 orang).
Tabel 4.9. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Bangsal Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Usaha
1. Perorangan 0 0,0 2. Kelompok 10 100
Total Jumlah 10 100 Tahun Mulai Usaha
1. 1970 – 1987 3 30,0 2. 1988 – 1993 3 30,0 3. 1994 – 2015 4 40,0
Total Jumlah 10 100 Siapa yang Merintis Usaha
1. Pribadi 2 20,0
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 46
2. Keluarga 8 80,0 Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Anak Kerbau
1. Tidak Ada 3 30,0 2. 1 – 2 ekor 4 40,0 3. 3 – 4 ekor 3 30,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 9 90,0 2. 1 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Betina
1. Tidak Ada 8 80.0 2. 2 - 4 ekor 2 20,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 9 90,0 2. 12 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 2 20,0 2. 1 – 3 ekor 4 40,0 3. 4 – 10 ekor 3 30,0 4. 14 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 9 90,0 2. 1 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 1 10,0 2. 2 – 4 ekor 5 50,0 3. 5 – 10 ekor 4 40,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Anak Kerbau
1. Tidak Ada 6 60,0 2. 2 ekor 3 30,0 3. 15 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau sapihan Betina
1. Tidak Ada 10 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 47
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 7 70,0 2. 2 – 5 ekor 3 30,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 9 90,0 2. 10 ekor 1 10,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 8 80,0 2. 1 ekor 2 20,0
Total Jumlah 10 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 5 50,0 2. 3 - 6 ekor 3 30,0 3. 10 - 13 ekor 2 10,0
Total Jumlah 10 100
Selanjutnya, Tabel 4.10 menyajikan status kepemilikan serta luaskandang, lahan pakan, dan lahan penggembalaan yang dimiliki oleh petani pemelihara kerbau rawa di Desa Bangsal.
Tabel 4.10. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Bangsal Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Kandang Milik Sendiri
1. 0 – 0,004 Ha 5 50,0 2. 0,0041 – 0,002 Ha 5 50,0
Total Jumlah 10 100 Kandang Kelompok
1. Tidak Ada 6 60,0 2. 0,006 Ha 4 40,0
Total Jumlah 10 100 Kandang Komunal
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Pakan Milik Sendiri
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Pakan Kelompok
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Pakan Komunal
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 48
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Gembala Milik Sendiri
1. 100 Ha 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Gembala Kelompok
1. Tidak Ada 10 100 Total Jumlah 10 100 Lahan Gembala Komunal
1. 100 Ha 10 100 Total Jumlah 10 100
4.1.5.3. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Kuro
Tabel 4.11. menyajikan profil usaha pemeliharaan kerbau rawa di Desa Kuro. Desa ini memiliki satu kelompok, yakni Kelompok Karya Bersama (12 anggota) dan 3 orang petani contoh yang tidak tergabung dalam kelompok. Rata-rata petani contoh memulai usaha pemeliharaan kerbau rawa pada tahun 1996 dan dirintis bersama oleh keluarga.
Jika dianalisis, jumlah ternak pribadi milik petani contoh rata-rata 6 ekor untuk kerbau dewasa betina. Sedangkan untuk kerbau titipan yang diusahakan oleh petani contoh pemelihara kerbau rawa di Desa Kuro, rata-rata tidak memelihara. Hanya ada sebagian kecil yang memelihara kerbau titipan, antara lain dengan kategori kerbau berukuran anak (2 orang), kerbau sapihan jantan (1 orang), kerbau sapihan betina (2 orang), kerbau muda betina (1 orang), kerbau dewasa jantan (1 orang) dan kerbau dewasa betina (4 orang).
Tabel 4.11. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Kuro Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Usaha
1. Perorangan 3 20,0 2. Kelompok 12 80,0
Total Jumlah 15 100 Tahun Mulai Usaha
1. 1982 – 1991 5 33,3 2. 1992 – 1997 5 33,3 3. 1998 – 2005 5 33,3
Total Jumlah 15 99,9 Siapa yang Merintis Usaha
1. Pribadi 7 46,7 2. Keluarga 8 53,3
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Anak Kerbau
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 49
1. Tidak Ada 9 60,0 2. 1 – 3 ekor 6 40,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 11 73,3 2. 1 - 2 ekor 4 26,7
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Betina
1. Tidak Ada 12 80,0 2. 1 - 4 ekor 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 12 80,0 2. 1 - 2 ekor 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 8 53,3 2. 1 – 3 ekor 6 40,0 3. 19 ekor 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 12 80,0 2. 1 – 2 ekor 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 1 6,7 2. 2 – 3 ekor 5 33,3 3. 4 – 8 ekor 6 40,0 4. 9 – 15 ekor 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Anak Kerbau
1. Tidak Ada 13 86,7 2. 2 – 4 ekor 2 13,3
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 14 93,3 2. 1 ekor 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau sapihan Betina
1. Tidak Ada 13 86,7 2. 2 – 3 ekor 2 13,3
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 15 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 50
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 14 93,3 2. 4 ekor 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 14 93,3 2. 3 ekor 1 6,7
Total Jumlah 15 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 11 73,4 2. 2 - 5 ekor 2 13,3 3. 8 - 9 ekor 2 13,3
Total Jumlah 15 100
Selanjutnya, Tabel 4.12 menyajikan status kepemilikan serta luaskandang, lahan pakan, dan lahan penggembalaan yang dimiliki oleh petani pemelihara kerbau rawa di Desa Kuro.
Tabel 4.12. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Kuro Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Kandang Milik Sendiri
1. 0,0012 – 0,0015 Ha 6 40,0 2. 0,0016 – 0,0036 Ha 4 26,7 3. 0,0037 – 0,005 Ha 5 33,3
Total Jumlah 15 100 Kandang Kelompok
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Kandang Komunal
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Lahan Pakan Milik Sendiri
1. Tidak Ada 1 6,7 2. 2 Ha 12 80,0 3. 10 Ha 2 13,3
Total Jumlah 15 100 Lahan Pakan Kelompok
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Lahan Pakan Komunal
1. Tidak Ada 3 20,0 2. 125 Ha 12 80,0
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 51
Total Jumlah 15 100 Lahan Gembala Milik Sendiri
1. Tidak Ada 12 80,0 2. 10 Ha 3 20,0
Total Jumlah 15 100 Lahan Gembala Kelompok
1. Tidak Ada 15 100 Total Jumlah 15 100 Lahan Gembala Komunal
1. Tidak Ada 3 20,0 2. 125 Ha 12 80,0
Total Jumlah 15 100
4.1.5.4. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Menggeris
Tabel 4.13. menyajikan profil usaha pemeliharaan kerbau rawa di Desa Menggeris. Desa ini memiliki satu kelompok, yakni Kelompok Harapan Bersama (13 anggota) dan 1 orang petani contoh yang tidak tergabung dalam kelompok. Rata-rata petani contoh memulai usaha pemeliharaan kerbau rawa pada tahun 1995 dan dirintis bersama oleh keluarga.
Jika dianalisis, jumlah ternak pribadi milik petani contoh rata-rata 1 ekor kerbau muda jantan, 3 ekor kerbau muda betina dan 8 ekor untuk kerbau dewasa betina. Sedangkan untuk kerbau titipan yang diusahakan oleh petani contoh pemelihara kerbau rawa di Desa Menggeris, rata-rata tidak memelihara. Hanya ada sebagian kecil yang memelihara kerbau titipan, antara lain dengan kategori kerbau berukuran anak (3 orang), kerbau sapihan betina (2 orang), kerbau muda betina (4 orang), kerbau dewasa jantan (2 orang) dan kerbau dewasa betina (5 orang).
Tabel 4.13. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa MenggerisTahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Usaha
1. Perorangan 1 7,1 2. Kelompok 13 92,9
Total Jumlah 14 100 Tahun Mulai Usaha
1. 1978 – 1994 5 35,7 2. 1995 – 1998 5 35,7 3. 1999 – 2006 4 28,6
Total Jumlah 14 100 Siapa yang Merintis Usaha
1. Pribadi 1 7,1 2. Keluarga 13 92,9
Total Jumlah 14 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 52
Jumlah Ternak Pribadi Anak Kerbau 1. Tidak Ada 8 57,1 2. 1 – 3 ekor 4 28,6 3. 4 – 6 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Betina
1. Tidak Ada 13 92,9 2. 2 ekor 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 7 50,0 2. 1 - 2 ekor 6 42,9 3. 3 – 4 ekor 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 2 14,3 2. 1 – 3 ekor 5 35,7 3. 4 – 6 ekor 5 35,7 4. 7 - 15 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 13 92,9 2. 1 ekor 1 7,1
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Betina
1. 2 – 7 ekor 4 28,6 2. 8 - 12 ekor 5 35,7 3. 18 - 22 ekor 5 35,7
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Anak Kerbau
1. Tidak Ada 11 78,6 2. 2 – 6 ekor 3 21,4
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau sapihan Betina
1. Tidak Ada 12 85,7 2. 1 – 9 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Jantan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 53
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 10 71,4 2. 2 - 5 ekor 2 14,3 3. 7 – 10 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 12 85,7 2. 1 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 9 64,3 2. 2 - 8 ekor 3 21,4 3. 13 - 27 ekor 2 14,3
Total Jumlah 14 100
Selanjutnya, Tabel 4.14 menyajikan status kepemilikan serta luaskandang, lahan pakan, dan lahan penggembalaan yang dimiliki oleh petani pemelihara kerbau rawa di Desa Menggeris.
Tabel 4.14. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Menggeris Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Kandang Milik Sendiri
1. 0,0048 – 0,0078 Ha 5 35,7 2. 0,0079 – 0,012 Ha 5 35,7 3. 0,013 – 0,014 Ha 4 28,6
Total Jumlah 14 100 Kandang Kelompok
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Kandang Komunal
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Pakan Milik Sendiri
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Pakan Kelompok
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Pakan Komunal
1. 0,04 Ha 1 7,1 2. 200 Ha 13 92,9
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 54
Total Jumlah 14 100 Lahan Gembala Milik Sendiri
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Gembala Kelompok
1. Tidak Ada 14 100 Total Jumlah 14 100 Lahan Gembala Komunal
1. 0,04 Ha 1 7,1 2. 200 Ha 13 92,9
Total Jumlah 14 100
4.1.5.5. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pampangan
Tabel 4.15. menyajikan profil usaha pemeliharaan kerbau rawa di Desa Pampangan. Desa ini memiliki satu kelompok, yakni Kelompok Sumber Harapan (12 anggota). Rata-rata petani contoh memulai usaha pemeliharaan kerbau rawa pada tahun 2002 dan dirintis bersama oleh keluarga.
Jika dianalisis, jumlah ternak pribadi milik petani contoh rata-rata 3 ekor untuk kerbau dewasa betina. Sedangkan untuk kerbau titipan yang diusahakan oleh petani contoh pemelihara kerbau rawa di Desa Pampangan, rata-rata tidak memelihara. Hanya ada sebagian kecil yang memelihara kerbau titipan, antara lain dengan kategori kerbau berukuran anak (1 orang), kerbau sapihan jantan (1 orang), kerbau sapihan betina (1 orang), kerbau muda betina (1 orang) dan kerbau dewasa betina (4 orang).
Tabel 4.15. Profil Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa di Desa Pampangan Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Jenis Usaha
1. Perorangan 0 0,0 2. Kelompok 12 100
Total Jumlah 12 100 Tahun Mulai Usaha
1. 1989 - 1999 4 33,3 2. 2000 – 2005 4 33,3 3. 2006 – 2014 4 33,3
Total Jumlah 12 99,9 Siapa yang Merintis Usaha
1. Pribadi 1 8,3 2. Keluarga 11 91,7
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Anak Kerbau
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 2 ekor 1 8,3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 55
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 1 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Sapihan Betina
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 5 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 7 58,4 2. 1 – 2 ekor 4 33,3 3. 30 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 1 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Pribadi Kerbau Dewasa Betina
1. 1 – 3 ekor 8 66,67 2. 4 – 5 ekor 3 25,0 3. 70 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Anak Kerbau
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 2 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Sapihan Jantan
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 2 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau sapihan Betina
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 6 ekor 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Jantan
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Muda Betina
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 20 ekor 1 8,3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 56
Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Jantan
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Jumlah Ternak Titipan Kerbau Dewasa Betina
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 42 ekor 1 8,3
Total Jumlah 22 100
Selanjutnya, Tabel 4.16 menyajikan status kepemilikan serta luaskandang, lahan pakan, dan lahan penggembalaan yang dimiliki oleh petani pemelihara kerbau rawa di Desa Pampangan.
Tabel 4.16. Status dan Luas Kandang, Lahan Pakan dan Lahan Gembala Desa Pampangan Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang) Persentase (%) Kandang Milik Sendiri
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 0,0264 Ha 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Kandang Kelompok
1. Tidak Ada 1 8,3 2. 0,0225 Ha 11 91,7
Total Jumlah 12 100 Kandang Komunal
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Lahan Pakan Milik Sendiri
1. Tidak Ada 11 91,7 2. 60 Ha 1 8,3
Total Jumlah 12 100 Lahan Pakan Kelompok
1. 97 Ha 1 8,3 2. 157 Ha 11 91,7
Total Jumlah 12 100 Lahan Pakan Komunal
1. 500 Ha 12 100 Total Jumlah 12 100 Lahan Gembala Milik Sendiri
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100 Lahan Gembala Kelompok
1. Tidak Ada 12 100 Total Jumlah 12 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 57
Lahan Gembala Komunal 1. 500 Ha 12 100
Total Jumlah 12 100
4.1.6. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa
Analisis profitabilitas digunakan untuk melihat potensi usaha pemeliharan kerbau rawa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pampangan. Analisis profitabilitas dilakukan dengan melihat nilai NPV, PI, IRR, BEP biaya dan BEP unit serta kontribusi margin yang dibagi berdasarkan status kelompok dan perorangan.
4.1.6.1. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok
Pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok membutuhkan investasi awal sebesar Rp. 406.340.000,- (Empat ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan asumsi usaha berdasarkan kegiatan pemeliharaan kelompok. Rincian asumsi biaya investasi dapat dilihat pada tabel 4.17. berikut.
Tabel 4.17. Asumsi Investasi Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
No. Komponen Jumlah Harga/Sat. Total Biaya
(Rp) Unit (Rp) 1 Kandang Kerbau 8.000.000
Bangunan (15 x 4 x 3) meter 1 7.500.000 7.500.000
Instalasi Listrik 1 250.000 250.000
Instalasi Air 1 250.000 250.000
2 Peralatan Kandang
1.400.000
Troli 1 300.000 300.000
Sekop 2 100.000 200.000
Selang 50 15.000 750.000
Ember 10 15.000 150.000
3 Bahan Indukan
360.000.000
Indukan Betina 15 18.000.000 270.000.000
Indukan Jantan 5 18.000.000 90.000.000
TOTAL 369.400.000
4 Biaya Kontengensi (10 % Biaya Investasi) 36.940.000 TOTAL BIAYA INVESTASI 406,340,000.0
Kemudian untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha pemeliharaan kerbau rawa, baik biaya tetap maupun biaya variabel dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 58
Tabel 4.18. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun 1 A. Biaya Tetap Upah Pekerja 50.400.000,- Penyusutan asset per tahun 2.966.667,-
Jumlah Biaya Tetap 53.366.667,- B. Biaya Variabel Pakan Konsentrat 25,200,000,- Obat-obatan dan vitamin 2,400,000,- Susu 3,840,000,- Listrik 900,000,- Air 900,000,-
Jumlah Biaya Variabel 33.240.000,- Jumlah Biaya Tetap + Biaya Variabel 86.006.667,-
Berdasarkan pemakaian asumsi biaya investasi, biaya tetap dan biaya varibel maka
dilakukan perhitungan terhadap profitabilitas kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa di Kecamatan Pampangan. Untuk kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa, diperoleh NPV dengan nilai positif (NPV>1) sebesar Rp. 772.911.745. Selanjutnya, diperoleh nilai IRR sebesar 30 persen. Jika dilihat dari nilai NPV dan IRR, maka kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa memiliki ruang yang luas terhadap tingkat pengembalian investasi sehingga kegiatan tersebut sangat layak untuk dilakukan.
Tabel 4.19. NPV dan IRR Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun
0 1 2 3
Cash Inflow 440.000.000 440.000.000 710.000.000
Cash Outflow 406.340.000 41.820.000 41.820.000 41.820.000
Net Cashflow IRR (406.340.000) 398.180.000 398.180.000 668.180.000
Net Present Value (NPV) Rp. 772.911.745
Internal Rate of Return (IRR) 30 % Dengan Hasil Perhitungan net B/C ratio untuk usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok adalah sebagaimana pada Tabel 4.20. sebagai berikut.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 59
Tabel 4.20. Net B/C Ratio Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun
0 1 2 3 Kumulatif CF (406.340.000) 398.180.000 398.180.000 668.180.000 Discount Factor 1,00 0,94 0,89 0,84 Present Value (406.340.000) 375.641.509,43 354.378.782,48 561.016.812,54 Kumulatif PV (406.340.000) (70.151.320,75) 247.007.810,61 772.911.744,73 Kelayakan Net Benefit Cost (BC) ratio 791,42 Pay Back Period (Tahun) 1,02
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai net B/C ratio yang menunjukkan angka 791,42 nilainya lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan usaha pemeliharaan kerbau rawa dikatakan sangat layak untuk diusahakan secara ekonomi. Dilihat dari nilai Pay Back Period (PBP) menunjukkan angka 1,02 tahun dimana artinya bahwa dalam masa kredit 3 tahun sangat memungkinkan bagi peternak untuk mengembalikan kredit, dimana kredit tersebut dapat dibayarkan kurang dari 2 tahun dan sisanya dapat digunakan untuk pengembangan usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok agar lebih maju lagi. Perhitungan BEP untuk usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.21. BEP Nilai rupiah dan Profit Margin Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Biaya Tetap (Rp) 53.366.667
Biaya Variabel (Rp) 33.240.000
Harga/Unit kategori Pedet (Rp) 8.000.000
BEP Unit kategori Pedet -1.116,32
Harga/Unit kategori Pedet (Rp) 18.000.000
BEP Unit kategori Indukan 42,17
Keterangan Tahun
1 2 3 Profit margin (%) 110,92% 111% 111% BEP (rupiah) 505.922.390,54 505.922.390,54 505.922.390,54 Profit margin % rata-rata 110,97%
Dari hasil analisis seluruh aspek tersebut hampir seluruhnya menunjukkan nilai
positif, maka usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok disimpulkan layak untuk dilaksanakan atau diusahakan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 60
4.1.6.2. Analisis Profitabilitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual
Pemeliharaan kerbau rawa pola individual membutuhkan investasi awal sebesar Rp. 106.590.000,- (Seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan asumsi usaha berdasarkan kegiatan pemeliharaan individu. Rincian penggunaan biaya dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut.
Tabel 4.22. Asumsi Investasi Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
No. Komponen Jumlah Harga/Sat. Total Biaya
(Rp) Unit (Rp) 1 Kandang Kerbau 5,500,000
Bangunan (8 x 4 x 3) meter 1 5,000,000 5,000,000
Instalasi Listrik 1 250,000 250,000
Instalasi Air 1 250,000 250,000
2 Peralatan Kandang
1,400,000
Troli 1 300,000 300,000
Sekop 2 100,000 200,000
Selang 50 15,000 750,000
Ember 10 15,000 150,000
3 Bahan Indukan
90,000,000
Indukan Betina 4.00 18,000,000 72,000,000
Indukan Jantan 1.00 18,000,000 18,000,000
TOTAL 96,900,000
4 Biaya Kontengensi (10 % Biaya Investasi) 9,690,000 TOTAL BIAYA INVESTASI 106,590,000
Kemudian untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha pemeliharaan kerbau rawa baik biaya tetap maupun biaya variabel dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut.
Tabel 4.23. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun 1 1. Biaya Tetap Upah Pekerja 16.800.000,- Penyusutan asset per tahun 2.133.333,-
Jumlah Biaya Tetap 18.933.333,- 2. Biaya Variabel Pakan Konsentrat 6.300.000,- Obat-obatan dan vitamin 600.000,- Susu 960.000,- Listrik 900.000,- Air 900.000,-
Jumlah Biaya Variabel 9.660.000,- Jumlah Biaya Tetap + Biaya Variabel 28.593.333,-
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 61
Berdasarkan pemakaian asumsi biaya investasi, biaya tetap dan biaya varibel maka dilakukan perhitungan terhadap profitabilitas kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa di Kecamatan Pampangan. Untuk kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa, diperoleh NPV dengan nilai positif (NPV>1) sebesar Rp. 279.970.045. Selanjutnya, diperoleh nilai IRR sebesar 41 persen. Jika dilihat dari nilai NPV dan IRR, maka kegiatan usaha pemeliharaan kerbau rawa memiliki ruang yang luas terhadap tingkat pengembalian investasi sehingga kegiatan tersebut sangat layak untuk dilakukan.
Tabel 4.24. NPV dan IRR Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun
0 1 2 3
Cash Inflow 122.000.000 122.000.000 194.000.000
Cash Outflow 106.590.001 13.230.000 13.230.000 13.230.000
Net Cashflow IRR 108.770.000 108.770.000 108.770.000
Net Present Value (NPV) Rp. 279.970.045
Internal Rate of Return (IRR) 41% Dengan Hasil Perhitungan net B/C ratio untuk usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individual adalah sebagaimana pada Tabel 4.25 berikut ini. Tabel 4.25. Net B/C Ratio Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di
Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Uraian Tahun
0 1 2 3 Kumulatif CF (106.590.001) 108.770.000 108.770.000 108.770.000 Discount Factor 1,00 0,94 0,89 0,84 Present Value 102.613.207,5 96.804.912,78 151.777.977,79 Kumulatif PV 90.132.075,47 175.162.335,35 315.832.150,03 Kelayakan Net Benefit Cost (BC) ratio 362,66 Pay Back Period (Tahun) 0,98
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai net B/C ratio yang menunjukkan angka 362,66 nilainya lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individual dikatakan sangat layak untuk diusahakan secara ekonomi. Dilihat dari nilai Pay Back Period (PBP) menunjukkan angka 0,98 tahun, dalam arti bahwa dalam masa kredit 3 tahun sangat memungkikan bagi petani untuk mengembalikan kredit, dimana kredit tersebut dapat dibayarkan kurang dari 1
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 62
tahun dan sisanya dapat digunakan untuk pengembangan usaha pemeliharaan kerbau rawa agar lebih maju lagi. Perhitungan BEP untuk usaha pemeliharaan kerbau rawa sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.26. BEP Nilai rupiah dan Profit Margin Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individual di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
Biaya Tetap (Rp) 18.933.333
Biaya Variabel (Rp) 9.660.000
Harga/Unit kategori Pedet (Rp) 8.000.000
BEP Unit kategori Pedet 76,96
Harga/Unit kategori Pedet (Rp) 18.000.000
BEP Unit kategori Pedet 9,36
Keterangan Tahun
1 2 3 Profit margin (%) 113,27% 113,27% 115,94% BEP (rupiah) 139.218.970,81 139.218.970,81 147.007.691,63 Profit margin % rata-rata 114,16%
Dari hasil analisis seluruh aspek tersebut seluruhnya menunjukkan nilai positif, maka usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individual disimpulkan layak untuk dilaksanakan atau diusahakan.
4.1.6.3. Analisis Sensivitas Pemeliharaan Kerbau Rawa
Kajian mengenai profitabilitas dan keekonomian usaha pemeliharaan kerbau rawa juga meliputi analisis sensitivitasnya. Analisis sensitivitas pada usaha pemeliharaan kerbau rawa ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh perubahan dari beberapa variabel terhadap NPV, IRR dan Net BC. Analisis sensitivitas dilakukan dengan membagi analisis berdasarkan pola usaha pemeliharaan, yakni pola kelompok dan pola individu.
1. Analisis Sensitivitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok
Dilihat dari Tabel 4.27, diketahui bahwa usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya, penurunan penerimaan maupun perubahan terhadap keduanya. Dari sisi biaya, meskipun biaya investasi dinaikkan hingga 80%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Selanjutnya dari sisi penerimaan, jika diturunkan sampai sebesar 100%, usaha pemelihaan kerbau rawa pola kelompok masih layak secara ekonomi dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 6,57% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 127,21. Kemudian, jika secara bersama-sama biaya produksi dinaikkan hingga sebesar 45%
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 63
dan penerimaan turun sebesar 50%, usaha pemeliharaan kerbau rawa masih layak dengan nilai NPV positif. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Tabel 4.27. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan 80% Rp 268.983.169 7,19% 233,68
2 Penerimaan turun 100 % Rp 38.631.846,57 6,57% 127,21
3 Biaya Produksi naik 45% dan Penerimaan turun 50%
Rp 270.821.776,63 7,10% 267,08
2. Analisis Sensitivitas Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Individu
Dilihat dari Tabel 4.28, diketahui bahwa usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individu tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya, penurunan penerimaan maupun perubahan terhadap keduanya. Dari sisi biaya, meskipun biaya produksi dinaikkan hingga 75%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Selanjutnya dari sisi penerimaan, jika diturunkan sampai sebesar 50%, usaha pemelihaan kerbau rawa pola kelompok masih layak secara ekonomi dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 6,57% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 127,21. Kemudian, jika secara bersama-sama biaya produksi dinaikkan hingga sebesar 35% dan penerimaan turun sebesar 25%, usaha pemeliharaan kerbau rawa masih layak dengan nilai NPV positif. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Tabel 4.28. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa Pola Kelompok Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Produksi dinaikkan 75% Rp 61.140.579,80 6,53% 124,61
2 Penerimaan turun 50 % Rp 38.631.846,57 6,57% 127,21
3 Biaya Produksi naik 35% dan Penerimaan turun 25%
Rp 54.319.160,59 7,21% 128,34
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 64
4.2. Pengembangan Biomas Pakan Kerbau di Lahan Gambut 4.2.1. Latar Belakang
Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang ada di Sumatera Selatan merupakan aset sumberdaya alam yang sangat besar dan secara signifikan menopang usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan juga hasil hutan non kayu bagi masyarakat sekitar. Peran strategis KHG terhadap masyarakat tersebut telah berlangsung sejak lama dan masih tetap berlangsung sampai saat ini. Salah satu komoditi unggulan KHG di Sumsel adalah kerbau rawa disamping komoditi lainnya. Keberadaan kerbau rawa dijumpai hampir di semua KHG yang ada di Sumsel. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Harun et al (2017) populasi kerbau rawa di KHG S. Saleh - S. Sugihan, KHG S. Sugihan - S. Lumpur, dan KHG S. Sebumbung - S Batok berjumlah sekitar 5.128 ekor, terbanyak di KHG S. Sebumbung - S Batok. Permasalahan yang dihadapi dalam budidaya kerbau rawa adalah penurunan populasi kerbau yang diduga ada kaitannya dengan sistem usaha petemakan yang masih dilakukan secara pengembalaan sistem tradisional. Akibat dari sistem pengembalaan tradisional maka kerbau rawa akan mengalami perpanjangan waktu kembali beranak yang lebih lama, kerbau kekurangan konsentrat penguat, dan lebih mudah terserang penyakit parasiter maupun penyakit infeksius dengan morbiditas tinggi kerap kali ditemukan menyerang temak kerbau (Natalia et al., 2006). Masalah lain yang dihadapi dalam mempertahanankan eksistensi kerbau rawa adalah alih fungsi padang gembala menjadi areal perkebunan kelapa sawit, perumahan/kampung, dan juga areal budidaya tanaman pangan.
Keterkaitan antara ketersediaan pakan kerbau sepanjang waktu dengan keberadaan rerumputan atau pakan pendukung di lokasi peternakan merupakan masalah pokok yang sangat mendesak untuk dicarikan solusi secepatnya.
Pakan yang dikonsumsi oleh kerbau ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim hujan, pakan kerbau keragamannya lebih banyak tumbuh, tetapi hujan yang berkepanjangan mengakibatkan banjir sehingga rumput menjadi terendam di dalam air dan kerbau sulit untuk menjangkau atau memakannya atau juga banyak jenis rumput tertentu mati. Pada musim kemarau yang panjang, masalah yang sering timbul adalah rumputan pakan banyak yang mati kekeringan sehingga ternak kerbau kekurangan pakan. Pada musim hujan, kelemahan lain yang dihadapi adalah adanya hama bagi hijauan pakan ternak yaitu berupa keong mas, dan di musim kemarau hama yang timbul adalah ulat. Kedua hama ini dapat mengurangi hijauan yang ada karena dimakan oleh hama tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, ternak ruminansia membutuhkan bahan kering pakan sebanyak rata-rata 3,5% dari bobot badannya. Berdasarkan patokan tersebut, maka seekor kerbau dewasa yang berbobot hidup 350 kg, akan membutuhkan sekitar 12,25 kg BK/hari (Suhubdy, 2007). Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kondisi
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 65
tanah, lahan, air dan agroklimatnya sangat berpengaruh terhadap produksi bobot kering pakan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kapasitas tampung efektif (effective carrying capacity) padang rumput alam sebagai sumber pakan utama. Untuk di wilayah timur Indonesia diasumsikan bahwa satu unit ternak (1 UT) setara dengan ternak dewasa yang berbobot hidup 350 kg, maka 1 ha lahan padang rumput tersebut hanya mampu menampung ternak herbivora (kerbau/sapi dewasa) sebesar 1 UT.
Jenis hijauan pakan ternak yang terdapat pada padang penggembalaan di Kalsel dan juga Sumsel didominasi rumput alam, diantaranya rumput (kumpai) jariwit, pepedasan, galunggung, kangkung, hiring-hiring, sumpilang, kumpai batu, kumpai miyang, kumpai juluk dan lain-lain. Secara umum, ketersediaan hijauan pakan di padang penggembalaan kerbau rawa di Kalimantan tergolong cukup tinggi dengan rataan berkisar 1,7–13 ton/ha/tahun pada musim kemarau dan 11,9-19,0 ton/ha/tahun pada musim hujan (Rohaeni, 2007). Berdasarkan data tersebut artinya produktivitas berat kering (BK) pakan berkisar antara 2,80 kg bk – 21,4 kg bk/ha/tahun pada musim kemarau. Sedangkan untuk musim hujan, produksi rumput pakan antara 19,6 kg bk – 35,2 kg bk. Dengan adanya fluktuasi yang relative besar untuk produksi pakan antara musim hujan dan kemarau jika dihubungkan dengan kebutuhan pakan harian kerbau maka permasalahan daya dukung padang gembala terhadap daya tamping kerbau selalu menjadi persoalan serius dalam meningkatkan populasi kerbau rawa di suatu lokasi padang gembala. Pengukuran produktivitas pakan kerbau rawa yang ada di padang gembala pada beberapa KHG di Sumsel belum ada sehinggga sangat sulit untuk menetapkan daya dukung dan daya tamping kerbau rawa system penggembalaan. Padahal informasi tersebut sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pelestarian kerbau rawa di Sumsel. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilaksanakan.
4.2.2. Tujuan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan informasi tentang jenis atau keragaman rumput pakan yang tumbuh di padang gembala saat recovery (awal musim hujan), padang gembala tergenang air (pertengahan musim hujan), padang gembala dan rumputan tenggelam air (akhir musim hujan), dan padang gembala kembali kering (awal musim kemarau),
2. Untuk mendapatkan produksi rumput berdasarkan jenis dari setiap fase pengamatan,
3. Untuk mengestimasi daya dukung dan daya tampung kerbau rawa di padang gembala
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 66
4.2.3. Metode Pelaksanaan
Penelitian ini tergolong sebagai riset aksi (action research) yang dilakukan di desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Lokasi penelitian terletak di padang gembala kerbau rawa yang lahannya milik penjaga ternak kerbau. Penelitian ini dimulai dari September 2018 sampai Juli 2019.
Pada lokasi padang gembala ditempatkan tiga petak pengamatan/percobaan. Petak percobaan disusun memanjang dari lahan yang relatif tinggi (darat) ke arah yang relatif rendah. Masing-masing petak di pagar dengan kayu yang kokoh. Adapun dimensinya adalah panjang 4 m, lebar 3 meter, dan tinggi 1,5 m. Kayu itu dilengkapi dengan kawat duri untuk mencegah masuknya kepala kerbau atau sapi ke dalam pagar.
Setiap petak diberi perlakuan yang berbeda, yaitu Petak 1) adalah petak yang diberi pupuk organik kotoran kerbau (10 kg/petak), petak 2) adalah petak yang diberi pupuk anorganik berupa pupuk lengkap NPK, 12, 12, 12 (2 kg/petak), dan petak 3) adalah petak yang diberi pupuk anorganik tunggal yaitu Urea (2 kg/petak). Aplikasi pupuk organik dan juga pupuk anorganik dilakukan setelah padang gembala terkena hujan deras.
Pengamatan dilakukan berdasarkan kondisi air di padang gembala (awal musim hujan), padang gembala tergenang air (pertengahan musim hujan), padang gembala dan rumputan tenggelam air (akhir musim hujan), dan padang gembala kembali kering (awal musim kemarau) atau periode pengamatan November 2018, Desember 2018, Januari - Februari 2019, dan April - Mei 2019. Parameter yang diamati adalah jenis rerumputan yang muncul dan diamati sebelum panen rumput, dan biomas masing-masing jenis rumput saat panen dengan cara menimbangnya.
Data disajikan berdasarkan jenis rerumputan yang ada atau hidup berbasis kondisi air di padang gembala, total biomas rerumputan yang dipanen berbasis kondisi air, jumlah total biomas yang diperoleh selama penelitian dari masing-masing petak percobaan. Berdasarkan data total biomas rerumputan yang terkumpul selama penelitian maka dapat dihitung atau diestimasi produksi biomas dari padang gembala kerbau rawa.
4.2.4. Pembuatan demplot biomas pakan kerbau di Lahan Gambut
Petak penelitian atau percobaan sebagai demplot biomas pakan kerbau rawa dibuat dengan ukuran petak 4 m x 3 m x 1,5 m yang bahannya adalah kayu bulat panjang yang diletakkan secara terpisah antar petak. Kondisi petak percobaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 67
Gambar 4.4. Bentuk dan posisi petak percobaan biomas pakan kerbau rawa Pada saat menjelang penelitian, kondisi rumput pakan ternak masih tergolong kering dan sangat sedikit yang hijau. Kehijauan mulai nampak setelah ada dua kali turun hujan saat awal September pada padang gembala (Gambar 4.5).
Gambar 4.5. Kondisi padang gembala dan rumput biomas pakan kerbau
4.2.5. Produksi biomas pakan kerbau
Sekitar pertengahan April 2018 (satu minggu) setelah petak dibuat terjadi hujan yang relatif deras sehingga dilakukan pemberian perlakuan Petak 1) kotoran kerbau (10 kg/petak), Petak 2) NPK, 12, 12, 12 (2 kg/petak), dan petak 3) Urea (2 kg/petak) dengan cara nenaburkannya secara merata. Pada 23 september 2018 (satu minggu) setelah penaburan pupuk ternyata petak yang diberi kotoran kerbau menunjukan recovery yang sangat cepat dengan kondisi pertumbuhan rumput yang lebih cepat dibandingan petak 2 dan petak 3. Secara umum penampilan dari petak 1, petak 2 dan petak 3 dapat dilihat pada Gambar 4.6.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 68
a. Petak yang diberi kotoran kerbau
b. Petak yang diberi pupuk NPK
c. Petak yang diberi urea
Gambar 4.6. Penampilan Petak percobaan Biomas pakan kerbau
Jenis pupuk berpengaruh terhadap percepatan recovery dan peningkatan jumlah spesies rumput dan biomas pakan (Tabel 4.29). Biomas yang diperoleh dari aplikasi pupuk organik, NPK dan Urea berturut-turut 18 kg, 6 kg dan 4 kg. Pupuk organik dapat meningkatkan jumlah spesies sampai dua kali lipat dan peningkatan biomas sampai empat kali lipat.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 69
Tabel 4.29. Spesies rumput yang tumbuh di petak perlakuan pupuk organik, NPK & Urea
No Spesies Nama Umum Famili Perlakuan
1 2 3 1 Alternanthera
philoxeroides Kremahan Amaranthaceae + +
2 Alternanthera sessilis Tolod Amaranthaceae + 3 Heliotropium indicum Buntut Tikus Boranginaceae + 4 Cyperus digitatus Rumput
Musang Cyperaceae + + +
5 Cynodon dactylon Grintingan Gramineae - - + 6 Digitaria ciliaris Cakar Ayam Gramineae + + - 7 Echinocloa colonum Rumput Tuton Gramineae + 8 Hymenachne
acutigluma Rumput Kumpai
Gramineae + +
9 Leersia hexandra Kalamenta Gramineae + 10 Saciolepis interupta Wuwudelan Gramineae + + + 11 Ludwigia octovalvis Cacabean Onagraceae + 12 Ludwigia adscendens Tapak Doro Onagraceae + 13 Oxalis barrelieri Calincing Oxalidaceae + 14 Hedyotis corymbosa Katepan Rubiaceae + +
Jumlah spesies 13 6 3 Keterangan: 1 = pupuk organik, 2 = pupuk NPK, 3 = Pupuk Urea, + = ditemukan, - = tidak ditemukan
Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perlakuan pupuk organik terhadap tanaman menghasilkan jumlah spesies yang lebih banyak dibandingkan dengan perlukuan pupuk lainnya, yakni sebanyak 13 spesies. Sedangkan perlakuan pupuk Urea menghasilkan jumlah spesies yang paling sedikit, yakni sebanyak 3 spesies. Hasil biomas saat panen dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. berikut
Gambar 4.7. Pengamatan spesies rumput saat panen biomas pertama dan kondisi
rumputan di petak yang diberi pupuk organik (1 bulan)
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 70
Gambar 4.8. Biomas yang didapat dari petak yang diberi pupuk organik dan biomas
yang sedang dikeringkan
4.3. Kajian Konsumsi Susu dan Produk Berbasis Susu 4.3.1. Latar Belakang
Susu merupakan salah satu sumber utama dari energi, protein dan lemak. Komoditas ini rata-rata berkontribusi dalam pemenuhan energi sebanyak 134 kkal/kapita per hari, protein 8 gram/kapita per hari dan lemak 7.3 gram/kapita per hari (UN FAO, 2013). Baik anak-anak maupun dewasa mengonsumsi susu dalam jumlah yang berbeda berdasarkan kebutuhan tubuh masing-masing. Susu kaya akan vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi pertumbuhan kulit dan tulang. Apabila tubuh manusia kekurangan vitamin-vitamin yang terkandung di dalam susu, maka akan berakibat pada penyakit xeroptalmia serta kerusakan otak dan kulit (Roth, 2013).
International Dairy Foods Association (IDFA) mendefinisikan susu sebagai material yang terdiri atas 87 persen air dan 13 persen padatan. Zat yang terkandung dalam setiap porsi susu diperkirakan sebanyak 3.7 persen lemak yang dapat melarutkan vitamin A, D, E dan K serta 9 persen padatan bukan lemak yang terdiri atas protein, karbohidrat dan mineral.
Setiap hari tubuh membutuhkan 2-3 porsi protein hewani. Untuk memenuhi kebutuhan satu porsi protein hewani dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi satu gelas susu sapi (200 gram) atau setengah gelas susu kerbau (100 gram) setiap harinya (Kementerian Kesehatan, 2014).
Menurut data Badan Pusat Statistik (2017), tingkat produksi susu di Indonesia terus meningkat dalam kurun tiga tahun terakhir, yakni dari 835.124.60 ton pada 2015 meningkat menjadi 912.735.01 ton pada tahun 2016 dan pada 2017 menjadi 920.093.41 ton. Namun, tingkat konsumsi susu per kapita di Indonesia masih terhitung rendah. Rata-rata konsumsi susu per kapita per bulan tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.30. Apabila tidak segera ditindak lanjuti, rendahnya tingkat konsumsi susu ini dapat mengakibatkan terjadinya lost generation
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 71
atau hilangnya suatu generasi. Hal tersebut merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Berbagai akibat rendahnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat terutama anak-anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan sudah tampak di masyarakat (Puslitbangtan, 2007), diantaranya stunting.
Tabel 4.30. Rata – rata Konsumsi Susu Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan per bulan, Tahun 2017
No. Komoditi Satuan Per Kapita
(bulan) Sumatera Selatan
(bulan)
1. Susu Segar Liter 0.024 0.007
2. Susu Cair Pabrik 250 ml 0.272 0.180
3. Susu Bubuk Kg 0.068 0.064
4. Susu Bubuk Bayi Kg 0.052 0.048
5. Susu Kental Manis 397 gr 0.356 0.636
6. Keju Ons 0.020 0.021
7. Hasil Lain Dari Susu Ons 0.020 0.005 Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2017
Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2017
Rendahnya tingkat konsumsi susu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sosial-budaya, ekonomi (harga susu yang relatif mahal), pola pikir, gaya hidup masyarakat dan lain sebagainya (Ariningsih, 2008). Tabel 4.30. menunjukkan bahwa tingkat konsumsi susu olahan lebih tinggi dibandingkan susu segar. Hal ini kemungkinan terjadi akibat masa simpan susu olahan yang lebih panjang bila dibandingkan dengan susu segar (Prastiwi dan Setiawan, 2016).
Hewan ternak yang pada umumnya dijadikan sebagai sumber produksi susu di Indonesia adalah sapi, kambing dan kerbau. Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kekayaan plasma nutfah berupa spesies kerbau asli Indonesia, yaitu Kerbau Pampangan. Kerbau memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan karena mampu bertahan hidup dengan pakan berkualitas rendah, mampu beradaptasi dengan iklim setempat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan parasit. Memiliki komoditas yang dapat dimanfaatkan hasil susunya tidak serta-merta membuat tingkat konsumsi susu masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan menjadi tinggi. Berdasarkan gambaran data mengenai rendahnya tingkat konsumsi susu dari masyarakat menyebabkan pencarian faktor terkait berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat konsumsi produk tersebut sangatlah penting untuk dilakukan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 72
4.3.2. Tujuan
Kajian tingkat konsumsi susu ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menghitung tingkat konsumsi susu rumah tangga di kawasan rawa lebak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi susu di kawasan rawa lebak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Mempelajari strategi dalam meningkatkan kecukupan konsumsi susu rumah tangga di kawasan rawa lebak Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4.3.3. Susu dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Susu
Susu adalah bahan pangan yang mengandung zat-zat penting bagi kehidupan manusia, yakni protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan faktor-faktor pertumbuhan (Resnawati, 2012). UN FAO dan WHO (2011) mendefinisikan susu sebagai sekresi normal kelenjar mamari/ambing mamalia atau cairan yang diperoleh dari pemerahan ambing tanpa dikurangi atau ditambahkan sesuatu, dimaksudkan untuk konsumsi sebagai susu cair atau untuk diproses lebih lanjut.
Susu merupakan material biologi yang sangat kompleks. Ia memiliki sistem multi fase atas beberapa kelompok unsur nutrisi dan teknologi yang signifikan. Susu juga dianggap sebagai sebuah sistem yang dinamis, hal ini dikarenakan sifatnya yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Susu mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan dianggap sebagai makanan pokok alami. Komoditas ini juga kaya akan agen protektif, enzim dan berbagai faktor pertumbuhan bagi makhluk hidup. Selama ribuan tahun manusia telah menjinakkan hewan-hewan mamalia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi susu dalam hidupnya (Huppertz dan Kelly, 2009)
Terdapat beberapa jenis ternak yang dapat dijadikan sebagai sumber produksi susu di Indonesia, yaitu sapi, kambing dan kerbau. Susu kerbau mengandung 4,5 gram protein, 8 gram lemak, 463 kkal dan 195 iu kalsium. Susu kerbau diketahui lebih kental bila dibandingkan dengan susu sapi, hal ini dikarenakan susu kerbau mengandung 16% bahan padat sedangkan susu sapi bahan padatnya hanya sebanyak 12% (Maryana, 2018). Jika dibandingkan dengan jumlah laktasi yang sama, kerbau akan menghasilkan susu dengan kadar lemak dan bahan padat bukan lemak lebih tinggi dibanding sapi lokal di India (Murti, 2002). Di Indonesia, produksi susu kerbau bervariasi antara 0.9-1.5 liter/ekor/hari (Matondang dan Talib, 2015). Produksi susu kerbau rawa atau kerbau pampangan berkisar antara 800 – 1.200 liter per laktasi dengan panjang laktasi 200 - 300 hari (Dinas Peternakan OKI, 2011).
Pandey dan Voskuil (dalam Damayanthi et al., 2014) menemukan bahwa rerata kandungan susu kerbau rawa lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Perbandingan kandungan susu kerbau rawa dan susu sapi disajikan pada Tabel 4.31.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 73
Tabel 4.31. Perbandingan Kandungan Kimia Susu Kerbau Rawa dan Susu Sapi
Parameter Kerbau Rawa Sapi Kadar protein (%) 5.41 - 0.37 3.4 Kadar lemak (%) 7.23 - 1.58 4 BKTL* (%) 10.61 - 0.78 4.4 Kadar air (%) 81.87 - 2.26 87.2 Berat jenis (Kg/m3) 1030 1030 *Berat Kering Tanpa Lemak Sumber: Pandey dan Voskuil dalam Damayanthi et al., 2014
Secara umum, susu kerbau memiliki komposisi yang sama dengan susu sapi dan ruminan lainnya, yaitu air, protein, lemak, laktosa, vitamin dan mineral, yang membedakan hanyalah proporsinya saja. Susu kerbau lebih kaya lemak dibanding susu sapi dan tidak memiliki kandungan karoten sehingga memiliki warna lebih putih dari susu sapi (Murti, 2002).
Sama halnya dengan susu sapi, susu kerbau juga dapat diolah lebih lanjut untuk
dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomis. Saat ini produk olahan susu kerbau yang dapat ditemukan di Indonesia antara lain dadih di Sumatera Barat, danke di Sulawesi Selatan, cologanti di Nusa Tenggara Barat, dan dali di Sumatera Utara. Selain menjadi produk olahan khas daerah, susu kerbau dapat diolah menjadi keju mozzarella (Destriana, 2008). Di wilayah Sumatera Selatan juga terdapat produk olahan dari susu kerbau yang disebut dengan gulo puan.
Perilaku konsumsi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan (Mangkunegara dalam Erni, 2013). Dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Konsumen”, Setiadi (2003) mendefinisikan
perilaku konsumen sebagai keterlibatan langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menggunakan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Menurutnya faktor yang mempegaruhi perilaku konsumen meliputi faktor budaya, sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.
Faktor Kebudayaan
Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling mendasari perilaku dan keinginan seseorang. Bila makhluk-makhluk hidup lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dapat dipelajari. Seseorang yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, preferensi, persepsi dan perilaku melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 74
Faktor Sosial
Faktor sosial meliputi 3 hal, yaitu kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status. Kelompok referensi seseorang terdiri atas seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh bak secara langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Dalam kehidupan seorang pembeli, keluarga terbagi atas dua, yakni kelurga orientasi dan keluarga prokreasi. Peran dan status seseorang umumnya berpartisipasi dalam suatu kelompok atau organisasi dimana posisinya diidentifikasikan dalam peran dan statusnya dalam kelompok tersebut.
Faktor Pribadi
Faktor pribadi meliputi 3 hal, yaitu umur dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Konsumsi seseorang terbentuk dari umur dan tahapan siklus hidup keluarga. Berdasarkan beberapa penelitian terakhir, orang dewasa mengalami perubahan tertentu saat mereka menjalani hidupnya. Pekerjaan akan menentukan seberapa besar pemasukan yang akan dimiliki oleh seseorang dalam periode tertentu, sehingga akan mempengaruhi perilaku konsumsinya. Keadaan ekonomi adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, harta dan tabungan serta kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap pengeluaran (lawan menabung). Gaya hidup adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapatan seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan”
yang berinteraksi dengan lingkungan. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responsnya terhadap lingkungannya yang relatif konsisten.
Faktor Psikologis
Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan sikap. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti rasa resah dan lapar. Kebutuhan juga ada yang bersifat psikogenik yang timbul akibat perasaan ingin diakui atau kebutuhan harga diri. Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana orang memilih, mengorganisasikan dan mengartikan informasi dalam menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu.
Secara makro, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga, antara lain faktor ekonomi (pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga dan perkiraan di masa depan), faktor demografi (jumlah penduduk dan komposisi penduduk), serta faktor non ekonomi (sosial-budaya) (Prasetyo, 2012).
Penelitian pola konsumsi susu pada anak di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa pola konsumsi susu anak terhadap karakteristik anak tidak
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 75
memiliki pengaruh. Kenaikan harga susu meningkatkan proporsi pengeluaran susu, sedangkan kenaikan harga daging dan harga telur menurunkan proporsi pengeluaran susu (Soeherman, 2015). Faktor sosial ekonomi rumah tangga tidak berpengaruh pada konsumsi susu.
Hasil penelitian Destriana (2008) menunjukkan bahwa umur, pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap perilaku konsumsi susu pada aspek frekuensi pembelian susu. Sedangkan sumber informasi, jenis dan bentuk serta merek susu berpengaruh terhadap perilaku konsumsi susu pada aspek jenis dan bentuk susu yang dikonsumsi.
Hasil penelitian Setiawan (2016) menyatakan bahwa konsumsi susu pada anak sekolah di Kota Bandar lampung dipengaruhi oleh pengeluaran susu, sikap anak terhadap susu, dan pengaruh merk.
Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan perilaku konsumtif remaja. Disebutkan bahwa jumlah dan frekuensi konsumsi susu secara signifikan berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan pendapatan per bulan, artinya peningkatan pendidikan dan pendapatan akan meningkatkan frekuensi dan jumlah konsumsi susu (Retnaningsih, 2008).
4.3.4. Lokasi Kajian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pampangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena kecamatan ini merupakan sentra pemeliharaan kerbau di Kabupaten OKI. Kerbau di Kecamatan Pampangan dipelihara sebagai usaha yang dapat menambah aset pihak yang mengusahakannya yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk memperoleh pendapatan tunai. Selain itu, kerbau yang dipelihara dapat diambil susunya untuk dikonsumsi, dijual atau diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
4.3.5. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian. Metode ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan cara mewawancarai responden menggunakan daftar pertanyaan.
Penarikan contoh yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 tahap, yaitu cluster sampling dan stratified random sampling. Cluster sampling digunakan untuk mengelompokkan populasi penelitian ke dalam 3 kluster desa berdasarkan sumberdaya dan/atau sumber mata pencaharian masyarakat, yaitu: (1) kluster desa dengan mata pencaharian berbasis kerbau rawa, (2) kluster desa dengan mata pencaharian berbasis sawah lebak (tidak ada kerbau), dan (3) kluster desa dengan mata
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 76
pencaharian berbasis kebun karet (tanpa kerbau). Dari setiap kluster desa kemudian dipilih masing-masing desa yang mewakili klusternya masing-masing. Dari setiap desa kemudian dipilih rumah tangga responden yang memiliki anak usia sekolah dasar (SD) berdasarkan 3 strata kelas pada sekolah dasar, yaitu (1) kelas 1 atau 2, (2) kelas 3 atau 4, dan (3) kelas 5 atau 6.
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap keluarga siswa sekolah dasar pada tiga dessa terpilih di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik sosio-demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan), tingkat konsumsi susu (jenis, merek dan frekuensi), perolehan susu, pembelian susu (frekuensi, jumlah, ukuran dan harga) dan preferensi konsumsi (jenis, lokasi pembelian, waktu konsumsi dan alasan mengonsumsi). Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu menghitung tingkat konsumsi susu, data konsumsi susu akan dianalisis secara deskriptif.
Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi susu akan digunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent). Dalam metode ini, yang menjadi variabel dependen adalah tingkat konsumsi susu. Sedangkan variabel independen meliputi usia, pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, selera, harga susu, harga barang lain dan sumber informasi. Persamaan penduga dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b2PU + b3Pd + b4Pdp + b1JAK + b5JR + b6LR + b7LP + b8LL + b8JK + E
Dimana: Y = Tingkat konsumsi susu α = Intercept b1-8 = Koefisien regresi PU = Pekerjaan Utama KK Pd = Pendidikan (SD; SMP; SMA; Sarjana) Pdp = Pendapatan (Rp/bulan) JAK = Jumlah anggota keluarga (n orang) JR = Jenis Rumah
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 77
LR = Luas Rumah (m2) LP = Luas Pekarangan (ha) LL = Luas Lahan yang dimiliki (ha) JK = Jumlah Kerbau yang dimiliki (ekor) E = Error
4.3.6. Perilaku Konsumsi Susu
Responden dalam kegiatan konsumsi susu adalah orangtua dari murid sekolah dasar di 3 Desa di Kecamatan Pampangan, yakni SDN 1 Pampangan, SDN 1 Bangsal dan SDN 1 Menggeris. Survey perilaku konsumsi susu dilakukan untuk mengetahui tentang frekuensi konsumsi susu yang dilakukan oleh Rumah Tangga ketiga desa di Kecamatan Pampangan.
Berdasarkan tabel 4.32, jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi susu sehari-hari sebanyak 47 RT dengan persentase 78,3 persen dan rumah tangga yang tidak mengkonsumsi susu sebanyak 13 RT dengan persentase 21,7 persen. Jenis susu yang dikonsumsi paling banyak adalah jenis susu kemasan sehari-hari yakni sebanyak 21 RT dengan persentase 31,0 persen dan jenis susu yang paling sedikit dikonsumsi adalah jenis susu kesehatan sebanyak 2 RT dengan persentase 3,0 persen. Alasan rumah tangga dalam mengkonsumsi susu paling banyak adalah untuk menjaga kesehatan, yakni sebanyak 19 RT dengan persentase sebesar 31,7 persen. Sebanyak 22 orang (36,7%) menganggap konsumsi susu adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Rata-rata rumah tangga responden atau sebanyak 28 RT (46,6 %) mengkonsumsi susu setiap hari dengan takaran 1 gelas setiap harinya. Rumah tangga responden sebanyak 31 RT (51,7%) membeli susu di toko/warung terdekat dan sebanyak 38 RT atau sebesar 52,1 persen mengkonsumsi susu dengan ukuran 101-450 gr. Rincian tetantang frekuensi perilaku konsumsi disajikan pada Tabel 4.32 berikut.
Tabel 4.32. Frekuensi perilaku konsumsi susu Desa Bangsal, Desa Pampangan dan Desa Menggeris di Kecamatan Pampangan Tahun 2018
No. Profil Jumlah (orang)
Persentase (%)
RT mengkonsumsi susu 1. Ya 47 78,3 2. Tidak 13 21,7 Total 60 100
Jenis susu yang dikonsumsi 1. Tidak Ada 13 19,1 2. Susu bayi/balita 8 11,7 3. Susu anak 19 28,0 4. Susu kemasan sehari-hari 21 31,0
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 78
5. Susu untuk kesehatan 2 3,0 6. Susu kental manis 5 7,3 Total 68 100
Bentuk susu yang dikonsumsi 1. Tidak Ada 13 18,0 2. Susu Bubuk 17 23,6 3. Susu kental manis 38 52,8 4. Susu UHT 2 2,8 5. Energen 1 1,4 6. Susu bantal 1 1,4 Total 72 100
Alasan konsumsi susu 1. Tidak Ada 13 21,7 2. Sudah menjadi kebiasaan 15 25,0 3. Untuk menjaga kesehatan 19 31,7 4. Pemenuhan gizi 10 16,7 5. Anjuran dokter 1 1,7 6. Keinginan 2 3,3 Total 60 100
Pengetahuan tentang kandungan susu 1. Tidak Tahu 22 19,1 2. Vitamin 34 29,6 3. Protein 18 15,6 4. Lemak 14 12,2 5. Karbohidrat 10 8,7 6. Mineral 17 14,8 Total 115 100
Tingkat kepentingan konsumsi susu 1. Tidak konsumsi 13 21,6 2. Sangat penting 12 20,0 3. Penting 22 36,7 4. Biasa saja 10 16,7 5. Tidak penting 3 5,0 Total 60 100
Frekuensi Konsumsi susu 1. Tidak konsumsi 13 21,7 2. Setiap hari 28 46,6 3. Seminggu n kali 13 21,7 4. Seminggu sekali 5 8,3 5. Lebih dari seminggu sekali 1 1,7 Total 60 100
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 79
Volume tiap konsumsi (gelas) 1. Tidak konsumsi 13 21,7 2. 1 gelas 42 70,0 3. 2 – 4 gelas 5 8,3 Total 60 100
Ukuran kemasan susu 1. Tidak konsumsi 13 17,8 2. 29 – 100 gr 5 6,8 3. 101 – 450 gr 38 52,1 4. 451 – 1000 gr 17 23,3 Total 73 100
Tempat membeli susu 1. Tidak konsumsi 13 21,6 2. Supermarket 6 10,0 3. Pedagang kaki lima 1 1,7 4. Toko/warung terdekat 31 51,7 5. Pasar 9 15,0 Total 60 100
Pendapat mengenai harga susu 1. Tidak konsumsi 13 21,6 2. Murah 10 16,7 3. Biasa saja 25 41,7 4. Mahal 12 20,0 Total 60 100
4.3.7. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Susu
Konsumsi susu merupakan suatu kegiatan yang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, hal tersebut berlaku baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Pada dasarnya konsumsi susu suatu rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal individu maupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, jumlah anggota keluarga (orang) , pekerjaan utama, pendidikan (SD; SMP; SMA; Sarjana), pendapatan (Rp/bulan), jenis rumah, luas Rumah (m2), luas Pekarangan (ha), luas Lahan yang dimiliki (ha) dan jumlah kerbau yang dimiliki (ekor).
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi susu secara langsung maupun tidak langsung dianalisis menggunakan model regresi linier berganda. Hasil analisis data disajikan pada Tabel 4.33.
Tabel 4.33. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi susu Tahun 2018
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 80
Variabel Koef. Regresi T Sig (constant) -.032 -.055 .956 Pekerjaan Utama KK .027 .476 .636 Pendidikan .053 1.719 .092* Pendapatan RT 3.814 .473 .638 Jumlah Anggota Keluarga .096 1.006 .319 Jenis Rumah -.127 -.377 .708 Luas Rumah .002 .401 .690 Luas Pekarangan .000 .056 .955 Luas Lahan yang dimiliki -.104 -.423 .674 Jumlah Kerbau yang dimiliki .082 1.567 .123 R2= 0,14 F statistik = 0,907
Keterangan : *signifikansi pada α = 0,10
Berdasarkan tabel 4.33, dari hasil analisis linier berganda diperoleh 1 variabel bebas yang berpengaruh terhadap volume konsumsi susu yakni, pendidikan. Sedangkan variabel pekerjaan utama KK, pendapatan RT, jumlah anggota keluarga, jenis rumah, luas rumah, luas pekarangan, luas lahan yang dimiliki dan jumlah kerbau yang dimiliki tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume konsumsi susu.
Selanjutnya untuk melihat apakah variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh secara bersama-sama terhadap volume konsumsi susu maka dilakukan uji F. Dapat dilihat uji F statistic (F hitung) yang diperoleh pada tabel 4.33 yaitu sebesar 0,907 yang kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui besarnya nilai F tabel harus ditentukan terleih dahulu nilai derajat bebasnya (df). Untuk derajat bebas pembilang (df1) didapat dengan menggunakan rumus df1 = k-1, sedangkan untuk derajat bebas penyebut (df2) didapat dengan menggunakan rumus df2 = n-k, dimana n merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah variabel bebas. Sehingga diperoleh df1= 8 dan df2 = 51. Nilai F tabel pada signifikansi 0,10 adalah sebesar 1,79 sedangkan dari hasil regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 0,907 yang berarti F hitung < F tabel. Maka apat diputuskan untuk terima H0, yang artinya secara bersama-sama variabel bebas dalam model tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat yakni volume konsumsi susu.
Kemudian setelah dilakukan uji estimasi model, dilakukan uji estimasi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji normalitas. Berikut uji asumsi klasik yang telah dilakukan.
1. Uji Multikolinearitas
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 81
Uji multikolinearitas umumnya dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai variance inflationfactor (VIF) dan nilai tolerance, yakni nilai kesalahan yang dibenarkan seara statistik. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.34.
Tabel 4.34. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2018
Variabel Collonearity Statistics
Tolerance VIF
(constant)
Pekerjaan Utama KK 0,773 1,294
Pendidikan 0,742 1,349
Pendapatan RT 0,832 1,201
Jumlah Anggota Keluarga 0,916 1,091
Jenis Rumah 0,756 1,322
Luas Rumah 0,627 1,596
Luas Pekarangan 0,716 1,398
Luas Lahan yang dimiliki 0,780 1,281
Jumlah Kerbau yang dimiliki 0,802 1,247
Suatu model persamaan dapat dilihat memiliki multikolinearitas apabila pada nilai tolerance masing-masing variabel bebas nilainya ada yang lebih besar dari 1 dan pada VIF nilainya ada yang lebih besar dari 10. Apabila nilai tolerance > 1 atau VIF > 10 maka terjadi multikoleniaritas. Setelah diuji, tidak terdapat variabel yang memiliki korelasi yang tinggi atau tidak terjadinya multikolinearitas. Sehingga model persamaan yang digunakan dapat dikatakan baik secara statistik.
2. Uji Heterokedastisitas
Dalam persamaan regresi linier berganda, salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap sama atau tidaknya varian dari residual antara observasi satu dengan observasi lainnya. Jika residual memiliki varians yang sama, maka disebut homokedastisitas dan jika residual memiliki varians yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Persamaan linier yang baik terjadi apabila tidak terjadi heterokedastisitas di dalamnya. Peneliti menganalisis uji asumsi heteroskedastisitas dilihat dari hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) untuk variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi – Y rill). Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 82
SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang tertentu. Berikut grafik scatterplot dari hasil uji pada SPSS.
Gambar 4.9. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan Gambar 4.9. dapat dilihat bahwa persamaan tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas karena titik-titik tidak terdapat kecenderunganmembentuk pola tertentu. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang diuji, baik.
3. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot yang diuji menggunakan SPSS.Asumsi normalitas yang diuji dalam asumsi klasik adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya.Kriteria sebuah (data) residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal P-P Plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar 4.10.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 83
Gambar 4.10. Grafik Normal P-Plot Hasil Uji Normalitas
Pada Gambar 4.10. dapat dilihat bahwa sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada data garis lurus (diagonal). Sehingga dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil ini sejalan dengan asumsi klasik dari regresi linier berganda yang digunakan.
Jadi kesimpulan dari uji asumsi klasik pada model regresi linier berganda adalah untuk melihat apakah persamaan yang digunakan baik atau tidak. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji normalitas,didapatkan hasil tidak terdapatvariabel yang memiliki hubungan korelasi, model persamaan bersifat homokedastisitas dan data menyebar secara normal.
Dari analisis regresi linier berganda, persamaan penduga dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = -0,032 + 0,027 PU + 0,053Pd + 3,814Pdp + 0,096JAK - 0,127JR + 0,002LR + 0,000LP – 0,104LL + 0,082JK
Dimana: Y = Tingkat konsumsi susu A = Intercept b1-8 = Koefisien regresi PU = Pekerjaan Utama KK
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 84
Pd = Pendidikan (SD; SMP; SMA; Sarjana) Pdp = Pendapatan (Rp/bulan) JAK = Jumlah anggota keluarga (n orang) JR = Jenis Rumah LR = Luas Rumah (m2) LP = Luas Pekarangan (ha) LL = Luas Lahan yang dimiliki (ha) JK = Jumlah Kerbau yang dimiliki (ekor)
Hasil dari analisis regresi diperoleh persamaan penduga yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif yakni, variabel pendidikan.
Setelah dilakukan uji F dan uji asumsi klasik pada model regresi linier berganda, maka selanjutnya dilakukan uji t untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat, yakni volume konsumsi susu. Pada penelitian ini, uji t dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap volume konsumsi susu. 4.3.7.1. Pekerjaan Utama KK
Variabel pekerjaan utama KK mengahsilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,027 dengan tingkat signifikan sebesar 0,636 yang lebih besar dari taraf nyata (α) yang
digunakan sebesar 10 persen (0,636>0,10). Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan utama KK berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.2. Pendidikan
Variabel pendidikan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,053 dengan tingkat signifikan sebesar 0,092 yang lebih kecil dari taraf nyata (α) yang digunakan
sebesar 10 persen (0,092<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif secara nyata terhadap volume konsumsi susu. Artinya, setiap penambahan satu satuan tahun pendidikan yang ditempuh maka akan menambah volume konsumsi susu sebesar 0,053 dengan asumsi variabel bebas yang lain dalam model regresi adalah tetap.
Hal tersebut dapat disebabkan karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk pribadi individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan akan pentingnya konsumsi susu akan semakin tinggi pula. Sehingga keinginan untuk kosumsi susu akan meningkat.
4.3.7.3. Pendapatan
Variabel pendapatan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 3,814 dengan tingkat signifikan sebesar 0,638 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang digunakan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 85
sebesar 10 persen (0,638<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.4. Jumlah Anggota Keluarga
Variabel jumlah anggota keluarga menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,096 dengan tingkat signifikan sebesar 0,319 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang
digunakan sebesar 10 persen (0,319<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.5. Jenis Rumah
Variabel jenis rumah menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,127 dengan tingkat signifikan sebesar 0,708 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang digunakan
sebesar 10 persen (0,708<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa jenis rumah berpengaruh negatif dan tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.6. Luas Rumah
Variabel luas rumah menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dengan tingkat signifikan sebesar 0,690 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang digunakan
sebesar 10 persen (0,690<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa luas rumah berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.7. Luas Pekarangan
Variabel luas pekarangan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan sebesar 0,955 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang
digunakan sebesar 10 persen (0,955<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa luas pekarangan berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.8. Luas Lahan yang Dimiliki
Variabel luas lahan yang dimiliki menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,104 dengan tingkat signifikan sebesar 0,674 yang lebih besar dari taraf nyata α)
yang digunakan sebesar 10 persen (0,674<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan yang dimiliki berpengaruh negatif dan tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.3.7.9. Jumlah Kerbau yang dimiliki
Variabel jumlah kerbau yang dimiliki menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,082 dengan tingkat signifikan sebesar 0,123 yang lebih besar dari taraf nyata α) yang digunakan sebesar 10 persen (0,123<0,10). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 86
kerbau yang dimiliki berpengaruh positif namun tidak secara nyata terhadap volume konsumsi susu.
4.4. Pengembangan Pengolahan Susu Kerbau Rawa 4.4.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Salah satu dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia adalah kerbau (Bulbalus bubalis). Kerbau adalah hewan ternak ruminansia besar dengan kemampuan berkembang dalam rentang agroekosistem luas yang dapat ditemukan hampir diseluruh daerah di Indonesia (Sitorus dan Anggreani, 2008).
Populasi ternak kerbau di Indonesia menempati urutan ke empat di Asia Tenggara setelah Filipina, Vietnam, dan Thailand (FAO, 2005). Kerbau yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan rumpun kerbau lumpur atau rawa (swamp buffalo) sebanyak 95%, sedangkan sisanya 5% termasuk rumpun kerbau sungai (river buffalo) (Sembiring et al., 2013). Kerbau lumpur atau rawa merupakan jenis kerbau yang memiliki kesukaan untuk berendam dalam rawa atau kubangan. Kerbau rawa memiliki sifat fisik yang khas yaitu tidak ditemukannya warna kulit coklat atau abu-abu coklat seperti pada kerbau sungai (Sitorus dan Anggreani, 2008).
Salah satu wilayah distribusi ternak kerbau rawa di Indonesia adalah Sumatera Selatan. Ternak kerbau rawa atau yang lebih dikenal kerbau Pampangan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi salah satu sumber perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKI pada tahun 2016 terdapat 9.354 ekor kerbau Pampangan yang tersebar di Kecamatan Pampangan, Jejawi, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, Pedamaran dan Air Sugihan. Pemanfaatan kerbau Pampangan di daerah Sumatera Selatan tidak terbatas hanya pada daging kerbau tetapi juga susunya sebagai sumber protein hewani. Potensi susu kerbau rawa yang dapat diperah rata-rata 1-1,5 liter per ekor per hari (Damayanthi et al., 2014).
Menurut Pandey dan Voskuil (2011), susu kerbau rawa mengandung lemak sebesar 7,23 ± 1,58% dan kadar protein sebesar 5,14 ± 0,37%, sedangkan susu kerbau sungai mengandung kadar lemak 4,13 ± 0,73% dan kadar protein 4,68 ± 0,41%. Lebih lanjut, kadar protein, lemak, mineral, dan vitamin susu kerbau rawa lebih unggul dari pada susu sapi (Walstra et al., 1999 dalam Han et al., 2012). Susu kerbau kaya akan kandungan mineral penting untuk pertumbuhan yaitu Ca, Fe, dan P, serta kandungan vitamin A (Febrina, 2010). Susu kerbau memiliki karakteristik lebih kental dibanding susu sapi karena mengandung 16% bahan padat, sedangkan bahan padat pada susu sapi hanya 12% (Matondang dan Talib, 2015).
Umumnya peminat susu kerbau rawa relatif sedikit. Kandungan nilai gizi yang tinggi pada susu kerbau rawa tidak menjadikan masyarakat beralih pada susu kerbau
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 87
rawa mengingat aroma amis yang dimiliki oleh susu kerbau rawa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bamualim et al. (2008) yang menyatakan bahwa rendahnya peminat susu kerbau rawa dikarenakan flavour yang tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan kandungan lemak yang tinggi.
Hingga saat ini, pemanfaatan susu kerbau di daerah Sumatera Selatan hanya sebatas pengolahan susu segar menjadi produk pangan tradisional yaitu “Gulo puan” dan “Sagon Puan”. Terbatasnya pilihan produk olahan susu kerbau yang ada menjadikan rendahnya minat masyarakat terhadap susu kerbau rawa. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengembangan produk olahan susu kerbau rawa agar dapat diterima masyarakat terutama oleh anak-anak mengingat pentingnya susu untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Minuman jeli merupakan salah satu produk pangan ringan yang disukai oleh anak-anak, remaja bahkan dewasa. Minuman jeli adalah produk minuman ringan berbentuk gel yang dibuat dari pektin, agar-agar, karagenan, gelatin atau senyawa hidrokoloid lainnya dengan penambahan gula, asam, dan atau tanpa bahan tambahan pangan lain yang diizinkan (SNI-01-3552-1994). Minuman jeli tidak hanya sekedar minuman tetapi juga dapat dikonsumsi sebagai minuman penunda lapar (Agustin dan Putri, 2014). Produk minuman jeli yang saat ini beredar dipasaran umumnya terbuat dari sari buah atau sayuran serta hanya mengedepankan kandungan serat pangan dan vitamin C. Diversifikasi minuman jeli berbahan dasar susu kerbau rawa diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap susu kerbau rawa
4.4.2. Tujuan
Dihasilkannya produk minuman jeli susu kerbau dengan teknologi pengolahan yang dapat diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat.
4.4.3. Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengembangan produk berbasis susu kerbau rawa menjadi produk minuman jeli ini dimulai dari preliminary research yaitu pembuatan minuman jeli susu dari enam formulasi konsentrasi susu dan gelling agent yang dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Preliminary research yang merupakan tahap awal ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi minuman jeli susu yang memiliki karakteristik mendekati produk minuman jeli komersial.
Metode yang dilakukan adalah uji sensoris (daya terima) panelis terhadap rasa, aroma dan tekstur dari enam formulasi minuman jeli susu kerbau rawa. Panelis pada uji sensoris ini adalah 25 orang mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Panelis diminta untuk
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 88
memberikan penilaian daya terima terhadap rasa, aroma dan tekstur dengan kategori 1untuk sangat tidak suka, 2 untuk tidak suka, 3 untuk suka, dan 4 untuk sangat suka.
Analisis karakteristik kimia minuman jeli susu kerbau rawa dilakukan pada perlakuan terbaik dari uji daya terima terhadap rasa, aroma dan tekstur. Karakteristik kimia yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, lemak dan protein.
4.4.4. Uji Sensoris (Daya Terima) Minuman Jeli Susu Kerbau
Uji sensoris (daya terima) yang dilakukan terhadap minuman jeli susu kerbau dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya uji sensoris lab dan uji sensoris lapangan. Kegiatan uji sensoris tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11 hingga gambar 4.13 berikut.
Gambar 4.11. Uji sensoris (daya terima) di lab penelitian UNSRI
Gambar 4.12. Bahan dan hasil produk minuman jeli susu kerbau rawa
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 89
Gambar 4.13. Uji sensoris (daya terima) terhadap anak SD di Kecamatan Pampangan
4.4.4.1. Aroma
Kesukaan panelis terhadap aroma minuman jeli susu kerbau dengan penambahan karegenan dan konsentrasi susu dan air yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 4.14.
Keterangan: A = karagenan 0,55%; susu:air = 40% : 60% B = karagenan 0,55%; susu:air = 50% : 50% C = karagenan 0,55%; susu:air = 60% : 40% D = karagenan 0,65%; susu:air = 40% : 60% E =karagenan 0,65%; susu:air = 50% : 50% F =karagenan 0,65%; susu:air = 60% : 40%
Gambar 4.14. Skor kesukaan aroma minuman jeli susu kerbau
Skor nilai rata-rata panelis terhadap aroma minuman jeli susu kerbau berkisar
antara 2,68 – 3,24 dengan kriteria tidak suka hingga suka. Nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap aroma minuman jeli susu kerbau adalah perlakuan D (karagenan 0,65%;susu:air = 40%:60%), dan nilai terendah adalah perlakuan C (karagenan 0,55%;susu:air = 60%:40%).
Perlakuan
Aroma
3.24 3.12 2.92 2.88 2.76 2.68
0
1
2
3
4
D E F A B C
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 90
Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman jeli susu kerbau menurun dengan semakin tingginya konsentrasi susu baik pada konsentrasi karagenan 0,55% maupun 0,65%. Hal ini terjadi karena penambahan konsentrasi susu kerbau yang tinggi akan meningkatkan aroma khas susu pada minuman jeli. Keadaan ini berbanding terbalik dengan penambahan konsentrasi karagenan dimana semakin tinggi konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada minuman jeli susu kerbau akan meningkatkan kesukaan panelis terhadap aroma minuman jeli. Hal ini disebabkan proses pemanasan pada pembuatan minuman jeli susu kerbau mengakibatkan terjadinya pengikatan komponen volatil oleh karagenan sehingga menyebabkan penurunan aroma yang tercium. Semakin tinggi konsentrasi karagenan maka semakin banyak komponen volatile yang terikat yang selanjutnya akan menyebabkan semakin sedikit aroma khas susu yang tercium oleh panelis (Riyanti et al., 2016).
4.4.4.2. Tekstur
Kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau dengan penambahan
karegenan dan konsentrasi susu dan air yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 4.15. Skor nilai rata-rata panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau berkisar antara 2,04 – 3,52 dengan kriteria tidak suka hingga suka. Nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau adalah perlakuan F (karagenan 0,65%;susu:air = 60%:40%), dan nilai terendah adalah perlakuan A (karagenan 0,55%;susu:air = 40%:60%).
Tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau menurun
dengan semakin rendahnya konsentrasi susu baik pada konsentrasi karagenan 0,55% maupun 0,65%. Hal ini disebabkan semakin banyak konsentrasi susu dalam formulasi minuman jeli susu kerbau akan meningkatkan protein yang akan membentuk gel dan jaringan gel pada saat proses pemanasan. Semakin banyak gel dan jaringan gel yang terbentuk akan memberikan tekstur minuman jeli susu kerbau yang kompak dan mantap.
Tekstur
Perlakuan
3.52 3.28 3.04
2.6 2.24 2.04
0
1
2
3
4
F E D C B A
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 91
Keterangan: A = karagenan 0,55%; susu:air = 40% : 60% B = karagenan 0,55%; susu:air = 50% : 50% C = karagenan 0,55%; susu:air = 60% : 40% D = karagenan 0,65%; susu:air = 40% : 60% E =karagenan 0,65%; susu:air = 50% : 50% F =karagenan 0,65%; susu:air = 60% : 40%
Gambar 4.15. Skor kesukaan tekstur minuman jeli susu kerbau
Tekstur minuman jeli susu kerbau perlakuan F (karagenan 0,65%;susu:air =
60%:40) telah memenuhi kriteria minuman jeli. Kriteria tekstur minuman jeli yang baik adalah mempunyai tekstur yang mantap saat dikonsumsi menggunakan sedotan, dan mudah hancur namun bentuk gelnya terasa di mulut. Gambar 4.15.menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau menurun dengan semakin tingginya konsentrasi karagenan yang ditambahkan. Karagenan merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan pembentuk gel pada pembuatan produk makanan (Restiana et al., 2014). Semakin rendah penambahan karagenan, maka semakin sedikit jumlah gugus hidroksil yang digunakan untuk membentuk gel. Dengan semakin sedikitnya gugus hidroksil ini maka kemampuan untuk membentuk disperse koloid (struktur double helix) lebih sedikit dan lemah, sehingga minuman jeli susu kerbau tidak dapat mempertahankan bentuknya sebagai gel (Febriyanti et al., 2015).
4.4.4.3. Rasa
Kesukaan panelis terhadap rasa minuman jeli susu kerbau dengan penambahan karegenan dan konsentrasi susu dan air yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 4.16. Skor nilai rata-rata panelis terhadap rasa minuman jeli susu kerbau berkisar antara 2,44 – 3,40 dengan kriteria tidak suka hingga suka. Nilai tertinggi kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau adalah perlakuan F (karagenan 0,65%;susu:air = 60%:40%), dan nilai terendah adalah perlakuan D (karagenan 0,65%;susu:air = 40%:60%).
Perlakuan
Rasa
3.4 3.2 2.96 2.84 2.6 2.44
0
1
2
3
4
F C E B A D
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 92
Keterangan: A = karagenan 0,55%; susu:air = 40% : 60% B = karagenan 0,55%; susu:air = 50% : 50% C = karagenan 0,55%; susu:air = 60% : 40% D = karagenan 0,65%; susu:air = 40% : 60% E =karagenan 0,65%; susu:air = 50% : 50% F =karagenan 0,65%; susu:air = 60% : 40%
Gambar 4.16. Skor kesukaan rasa minuman jeli susu kerbau
Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman jeli susu kerbau menurun
dengan semakin rendahnya konsentrasi susu baik pada konsentrasi karagenan 0,55% maupun 0,65%. Hal ini disebabkan semakin banyaknya konsentrasi susu dalam formulasi minuman jeli susu kerbau akan meningkatkan lemak pada minuman jeli susu kerbau yang selanjutnya akan memberikan peningkatan rasa enak.
4.4.5. Analisis Kandungan Kimia Minuman Jeli Susu Kerbau Rawa Berdasarkan uji sensoris maka perlakuan terbaik dari minuman jeli susu kerbau rawa adalah perlakuan F yaitu minuman jeli susu kerbau rawa dengan formulasi penambahan karegenan 0,65% dengan rasio konsentrasi susu dan air adalah 60% dan 40%. 4.4.5.1. Kadar air
Air merupakan komponen yang penting dalam bahan makanan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta citarasa makanan. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan daya terima, kesegaran dan daya tahan bahan makanan. Kadar air minuman jeli susu kerbau yaitu 77,60±0,26%. 4.4.5.2. Kadar abu
Kadar abu minuman jeli susu kerbau yaitu 0,79±0,00%. Kadar abu suatu produk pangan menunjukkan kandungan mineral pada produk pangan tersebut. Minuman jeli susu kerbau banyak mengandung mineral yang terdapat pada susu kerbau yaitu Ca, Fe dan P yang merupakan mineral utama yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu minuman ini juga mengandung mineral yang dikontribusikan oleh karagenan.
Karagenan merupakan senyawa yang termaksud dalam kelompok polisakarida galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut. Berdarkan FAO dan EEC kadar abu karagenan berkisar antara 15-24% dan FCC menetapkan kadar abu maksimal karagenan adalah 35%. Kadar abu menunjukan besarnya kandungan mineral pada karagenan yang tidak terbakar selama proses pengabuan. Rumput laut sebagai bahan utama karagenan termaksud bahan pangan yang mengandung mineral yang cukup
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 93
tinggi seperti Na, Ca, K, Cl, Mg, Fe, S, dan trace element berupa iodium (Bunga et al., 2013).
4.4.5.3. Protein
Protein minuman jeli susu kerbau yaitu 4,23±0,01%. Kadar protein minuman jeli susu kerbau dipengaruhi oleh kadar protein awal dan proses pengolahan. Semakin besar kandungan protein awal pada produk minuman jeli susu kerbau maka akan semakin besar pula kadar protein yang terdapat dalam produk minuman jeli susu kerbau. Gambar 7 menunjukkan semakin besar perbandingan air : susu semakin menurun kadar proteinnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh penambahan air yang berlebih pada rasio air dan susu. Menurut Palupi et al. (2007), protein mampu mengikat air sehingga protein akan larut dalam air.
Susu kerbau sebagai salah satu bahan utama pembuatan minuman jeli susu kerbau mengandung protein sebesar 4,57% dalam 100 mL. Adanya penurunan kadar protein pada produk minuman jeli susu kerbau dibandingkan dengan susu kerbau murni disebabkan oleh proses pengolahan minuman jeli susu kerbau tersebut. Protein dapat rusak oleh panas yang berlebih, bahan kimia, pengadukan yang berlebih dan adanya asam dan basa (Warsito et al., 2014). Pada proses pengolahan minuman jeli susu kerbau, susu kerbau murni ditambahkan dalam larutan jeli pada suhu 65°C. Hal ini menyebabkan turunnya kandungan protein. Protein akan mengalami kerusakan apabila dipanaskan pada suhu 50°C atau lebih (Poedjiadi dan Supriyanti, 2005).
4.4.5.4. Lemak
Lemak minuman jeli susu kerbau yaitu 9,64±0,16%.Menurut Sunarlim dan Setiyanto (2001) kadar lemak suatu makanan dipengaruhi oleh kadar lemak dari bahan dasar yang digunakan. Susu kerbau sebagai bahan utama pembuatan minuman jeli susu kerbau mengandung lemak sebesar 10,17% dan kandungan lemak karagenan sebagai hidrokoloid sebesar 1,78% (Murdinah, 2009).
4.4.5.5. Karbohidrat
Karbohidrat minuman jeli susu kerbau yaitu 7,71±0,34%. Kandungan karbohidrat minuman jeli susu kerbau ditentukan dengan metode by difference dimana penentuan kadar karbohidrat dengan perhitungan melibatkan kadar air, abu, protein dan lemak. Semakin tinggi kadar air, abu, protein dan lemak suatu produk maka akan semakin rendah kadar karbohidratnya. 4.4.5.6. Kalori
Kalori minuman jeli susu kerbau yaitu 135±1Kkal per 100 mL. Minuman jeli susu kerbau ini dapat memenuhi 7,65% AKG (persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2.150 Kkal).
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 94
4.4.6. Analisis Profitabilitas Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau
Usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau membutuhkan investasi awal sebesar Rp. 22.324.075,- (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah). Rincian asumsi biaya investasi dapat dilihat pada tebel 4.35. berikut.
Tabel 4.35. Asumsi Investasi Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau Tahun 2018
No. Uraian Jumlah Harga/Satuan (Rp/satuan)
Total Biaya (Rp)
A. Investasi 22.324.075 1 Kompor Gas TDC 1 1750.00 175.000 2 Tabung Gas 1 57.000 57.000 3 Regulator Gas 1 70.000 70.000 4 Panci Halco 36 cm 1 223.650 223.650
5 Stainless Steel Stockpot 28 cm
2 316.800
633.600 6 Spatula 2 43.900 87.800
7 Harnic Kitchen Scale (Timbangan Digital)
1 199.800 199.800
8 Gelas Takar 2 8.500 17.000 9 Thermometer Digital 1 72.900 72.900
10 Storage Jar Lion Star 3,5 L 2 33.500 67.000 11 Cool Box 22 liter 1 410.000 410.000 12 Cup Sealer Eton ET-D8 1 1.198.000 1.198.000
13 Showcase Allure SCN 148 Polytron 140 L
1 3.489.000 3.489.000
14 Alat Pasteurisasi 1 15.000.000 15.000.000 18 Milk Can 15L 1 551.325 551.325 19 Pompa Electric Galon Mineral 1 72.000 72.000
Kontingensi 10% 2.232.407,5 Total Biaya Investasi 22.324.075 Kemudian untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau, baik biaya tetap maupun biaya variabel dapat dilihat pada tabel 4.36 berikut. Tabel 4.36. Asumsi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Usaha Pengolahan Minuman Jeli
Susu Kerbau Tahun 2018
No. Uraian Jumlah Harga/Satuan (Rp/satuan)
Total Biaya (Rp/tahun)
1 BiayaTetap 24.820.800
Isi Tabung Gas Bright 1 60.000 720.000
Lip Cup Plastik Sealer 1 336.500 4.038.000
Cup Plastik 1800 1.000 1.080.000
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 95
Pipet plastic 6 15.000 1.080.000
Baterai Panasonic UM 1 UEA
1 16.900 202.800
Listrik 1 75.000 900.000
Air 1 900.000 10.800.000
Upah Pembuat Produk 2 250.000 6.000.000
2 Biaya Variabel 12.456.000
Rose Brand Gula Pasir (bungkus) 12 15.000 2.160.000
Nutrijell coklat (bungkus)
24 3.500 1.008.000
Nutrijell strawberry (bungkus)
24 3.500 1.008.000
Marjan syrup Coco Pandan (botol)
2 20.000 480.000
Air Mineral Alfa (Galon) 2 25.000 600.000
Susu Kerbau (liter) 30 20.000 7.200.000
Total Biaya Tetap + Biaya Variabel 37.276.800
Berdasarkan pemakaian asumsi biaya investasi, biaya tetap dan biaya varibel maka
dilakukan perhitungan terhadap profitabilitas kegiatan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau. Untuk kegiatan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau, diperoleh NPV dengan nilai positif (NPV>1) sebesar Rp. 31.262.439,89. Selanjutnya, diperoleh nilai IRR sebesar 25 persen. Jika dilihat dari nilai NPV dan IRR, maka kegiatan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau memiliki ruang yang luas terhadap tingkat pengembalian investasi sehingga kegiatan tersebut sangat layak untuk dilakukan.
Tabel 4.37. NPV dan IRR Usaha Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau Tahun 2018
Uraian Tahun
0 1 2 3 4 5
NCF (61.833.282) 27.523.200 27.523.200 27.523.200 27.523.200 34,014,160
DF 1,00 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75
PV (61.833.282) 25.965.283 24.495.550 23.109.009 21.800.952 25.417.359 Kelayakan Net B/C 1,95
Net Present Value (NPV) Rp. 22.860.389,58
Internal Rate of Return (IRR) 28 %
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai net B/C ratio yang menunjukkan angka 1,95 nilainya lebih besar daripada 1, maka dapat disimpulkan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau dikatakan layak untuk diusahakan secara ekonomi.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 96
4.4.7. Analisis Sensitivitas Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau Rawa
Kajian mengenai profitabilitas dan keekonomian usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa juga meliputi analisis sensitivitasnya. Analisis sensitivitas pada usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh perubahan dari beberapa variabel terhadap NPV, IRR dan Net BC.
Tabel 4.38. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinanan Situasi Pada Pengolahan Minuman Jeli Susu Kerbau Rawa Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan 14% Rp 1.073.407 12,70% 1,41
2 Penerimaan turun 12 % Rp 1.259.098,12 12,92% 1,42
3 Biaya Produksi naik 7% dan Penerimaan turun 6%
Rp 1.166.252,44 12,80% 1,41
Dilihat dari Tabel 4.38, diketahui bahwa usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya, penurunan penerimaan maupun perubahan terhadap keduanya. Dari sisi biaya, meskipun biaya investasi dinaikkan hingga 14%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Selanjutnya dari sisi penerimaan, jika diturunkan sampai sebesar 12%, usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa masih layak secara ekonomi dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 12,92% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 1,42. Kemudian, jika secara bersama-sama biaya produksi dinaikkan hingga sebesar 7% dan penerimaan turun sebesar 6%, usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa masih layak dengan nilai NPV positif. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi biaya daripada sisi penerimaan.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 97
V. ANALISIS PROFITABILITAS DAN KEEKONOMIAN TANAMAN
PALUDIKULTUR
5.1. Monitoring Pilot Project Paludikultur dan Restorasi Terintegrasi 5.1.1. Latar Belakang
Salah satu upaya untuk melakukan restorasi lahan gambut yang sudah mengalami degradasi adalah dengan penerapan konsep Paludikultur dan agroforestry. Paludikultur merupakan salah satu sistem dan/atau teknik rehabilitasi dan restorasi hutan rawa gambut, yaitu dengan memulihkan kondisi gambut menjadi basah kembali dengan menutup saluran-saluran drainase dan menanam jenis-jenis lokal (Joosten et al., 2012 dalam Tata & Susmianto, 2016; Suryadiputra et al., 2005 dalam Tata & Susmianto, 2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) menyatakan pengembangan Paludikultur dapat memanfaatkan tanaman semusim dengan kemampuan tumbuh baik pada lahan gambut, antara lain tanaman nenas dan lidah buaya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penanaman secara monokultur dan atau polikultur (multiple cropping). Beberapa keuntungan dari sistem tumpangsari antara lain pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok, peningkatan produksi total persatuan luas karena lebih efektif dalam penggunaan cahaya, air serta unsur hara, disamping dapat mengurangi resiko kegagalan panen dan menekan pertumbuhan gulma, dan pada akhirnya ekosistem yang terbentuk menjadi lebih kompleks dan lebih tahan terhadap perubahan faktor luar.
Keberhasilan melakukan restorasi lahan gambut melalui sistem paludikultur melalui pola agroforestry dengan sistem tumpang sari juga sudah dilakukan oleh Bastoni dan Tim Balai Litbang LHK Palembang di wilayah Sepucuk Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir). Berdasarkan keberhasilan ini ada beberapa tanaman kehutanan yang dapat direkomendasikan yaitu Jelutung, Ramin, Punak sedangkan untuk tanaman budidaya dapat digunakan tanaman Nenas, Jagung, Lengkuas, Kunyit, Singkong, dan Pisang (Bastoni dan Tim Peneliti Balai Litbang LHK Palembang, 2017).
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sejak tahun 2017 BRG bekerjasama dengan Unsri membuat pilot proyek Paludikultur ini. Dari banyak tanaman yang dicobakan di lahan pilot proyek tersebut, tanaman yang tumbuh adalah Jelutung, Meranti Merah, Nenas, dan Gelam. Lahan yang digunakan seluas 8 hektar. Agar kegiatan ini berhasil dan berkelanjutan maka perlu diperlukan pemeliharaan dan monitoring terhadap lahan dan perkembangan tanaman yang tumbuh disamping pengamatan tinggi muka air.
5.1.2. Tujuan
Kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk:
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 98
a) Memelihara tanaman yang tumbuh dan juga melakukan penyulaman tanaman yang mati.
b) Melakukan ujicoba tanaman sela yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. c) Mengamati pertumbuhan tanaman, perubahan muka air dan pemeliharaan sekat
kanal.
5.1.3. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode observasi secara langsung di lapangan dengan melibatkan masyarakat petani di sekitar pilot proyek.
5.1.4. Hasil Kegiatan 5.1.4.1. Monitoring hasil kegiatan penanaman tahun 2017
Kegiatan yang dilaksanakan dalam kajian ini diawali dengan kegiatan monitoring lapangan demplot Pilot Project Implementasi Paludikultur dan Restorasi Terintegrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Monitoring lapangan yang telah dilaksanakan pada kedua demplot pilot project tersebut meliputi kegiatan-kegiatan seperti pengamatan pertumbuhan tanaman, pengukuran lingkar batang, diameter dan tinggi tanaman, dan pengukuran pH, kedalaman gambut dan muka air tanah.
Pengamatan Pertumbuhan Tanaman
Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman disajikan pada Tabel 5.1. Tanaman yang diamati pertumbuhannya meliputi Jelutung dan Meranti pada lokasi pilot project paludikultur dan restorasi terintegrasi.
Tabel 5.1. Jumlah tanaman yang hidup pada waktu monitoring Tahun 2018
No. Jenis Tanaman Jumlah tanaman yang hidup
1. Jelutung 904
2. Meranti 368
3. Pulai 359
Pengukuran Lingkar Batang, Diameter danTinggi Tanaman
Jenis tanaman yang diukur meliputi Jelutung (Dyera lowii), Pulai (Shorea pauciflora), dan Meranti Merah (Shorea pauciflora). Hasil pengukuran lingkar, diameter dan tinggi tanaman disajikan pada Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 5.4.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 99
Tabel 5.2. Hasil pengukuran tanaman Jelutung pada lokasi pilot project Tahun 2018
No. Sampel Lingkar batang
(cm) Diameter batang
(cm) Tinggi tanaman
(cm) 1 5 1,59 110 2 4 1,27 114 3 5,7 1,82 63 4 4,8 1,53 80 5 4,6 1,46 85 6 4,5 1,43 63 7 3,6 1,15 78,5 8 3,2 1,02 82,6 9 3 0,96 70 10 5 1,59 92
Rerata 4,34 1,38 83,81
Tabel 5.3. Hasil pengukuran tanaman Meranti pada lokasi pilot project Tahun 2018
No. Sampel Lingkar batang
(cm) Diameter batang
(cm) Tinggi tanaman
(cm) 1 3,5 1,11 109 2 5 1,59 123 3 6 1,91 141 4 4,8 1,53 107 5 3 0,96 94 6 3,6 1,15 96 7 2,8 0,89 91 8 3,4 1,08 102 9 5 1,59 119 10 3,6 1,15 90
Rerata 4.12 1,30 107,20
Tabel 5.4. Hasil pengukuran tanaman Pulai pada lokasi pilot project Tahun 2018
No. Sampel Lingkar batang
(cm) Diameter batang
(cm) Tinggi tanaman
(cm) 1 3 0,96 114 2 4 1,27 96 3 4,7 1,50 108 4 3,5 1,11 63 5 4,7 1,50 120 6 5 1,59 77 7 4 1,27 170 8 3,8 1,21 78 9 5 1,59 208 10 2 0,64 97
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 100
Rerata 3,97 1,26 113,10
Pengukuran pH, kedalaman gambut dan muka air tanah
Hasil pengukuran pH baik pada lahan Paludikultur maupun lahan Restorasi
Terintegrasi, pH tanah masih berkisar antara 3 – 4. Posisi gambut pada lahan
Paludikultur rata-rata lebih dalam dari pada lahan Restorasi Terintegrasi. Sedangkan
muka air tanah rata-rata pada lahan Paludikultur lebih tinggi dari pada lahan Restorasi
Terintegrasi. Makin dalam posisi gambut makin tinggi muka air tanah.
Tabel 5.5. Hasil pengukuran pH, kedalaman gambut dan muka air tanah pada bulan September 2018
Lokasi Pilot Project Sampel Tanah pH Kedalaman
Gambut (cm) Muka Air
(cm)
Paludikultur 6 Titik 3 - 4 130 -140 50
Restorasi Terintegrasi 6 Titik 3 - 4 100 - 110 75
5.1.4.2. Ujicoba penanaman beberapa tanaman sela di sekitar tanaman utama
Kegiatan ujicoba tanaman sela dilakukan dengan menanam tanaman pangan yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Tanaman yang di ujicoba terdiri dari tanaman padi (Oryza sativa), jagung (Zea mays), nenas (Ananas comosus), bawang merah (Allium cepa), dan kangkung (Ipomoea aquatica). Penanaman tanaman tersebut dilakukan pada lahan di sekitar tanaman utama sebagai demplot dengan ukuran dan pola tanam yang berbeda tergantung dengan jenis tanamannya. Hasil uji coba penanaman berbagai jenis tanaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1 sampai dengan Gambar 5.6.
Gambar 5.1. Kondisi areal pertanaman
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 101
Gambar 5.2. Pertumbuhan tanaman padi: tanaman padi yang ditanam dengan sistem
tugal (kiri); tanaman padi yang ditanam dengan tebar langsung (sonor) (kanan)
Gambar 5.3. Pertumbuhan tanaman Jagung
Gambar 5.4. Pertumbuhan tanaman Nenas
Gambar 5.5. Pertumbuhan tanaman Bawang merah
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 102
Gambar 5.6. Pertumbuhan tanaman Kangkung
Ketika dilakukan pengamatan langsung di areal penanaman, lahan tergenang
sekitar 20 cm. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, telah terjadi hujan lebat pada malam harinya. Berdasarkan pengamatan, tanaman padi dan nanas tumbuh dengan baik (Gambar 5.7).
Gambar 5.7. Tanaman padi dan nanas yang kelihatan tumbuh dengan baik Padi yang dipupuk dan dikapur memperlihatkan pertumbuhan yang lebih subur
daripada yang tidak dipupuk, apalagi jika dibandingan dengan tanaman yang dilakukan oleh petani lokal dengan sistem tebar.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 103
5.2. Analisis Profitabilitas dan Keekonomian Komoditas Paludikultur 5.2.1. Latar Belakang
Ekosistem gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat penting perannya dalam mempertahankan kelestarian lingkungan khususnya yang terkait dengan isu pemanasan global. Fungsi lahan gambut yang salah satunya adalah sebagai penyerap emisi gas karbon menjadikan ekosistem ini harus dikelola dengan tepat agar fungsi utamanya tidak rusak. Kerusakan gambut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pembukaan lahan gambut menjadi perkebunan, pembukaan kanal, kebakaran hutan dan lahan serta pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan karakteristik gambut itu sendiri (Nduru, 2018). Asterina (2017). Pada tahun 2015 Indonesia mengalami kemarau panjang yang pernah terjadi juga pada tahun 1998. Kemarau tahun 2015 dipengaruhi oleh gelombang panas El Nino. Dampak dari El Nino adalah beberapa wilayah menjadi rentan mengalami kebakaran hutan.
Fenomena kebakaran hutan telah terbukti sangat berhubungan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan kegemaran bermain dengan api (fire maniac) (Akbar, 2004; Saharjo, 2006; Usup, 2006). Luas lahan yang terbakar itu diperkirakan juga termasuk kawasan perkebunan. Faktor kepentingan ekonomi berperan dalam menurunkan luas lahan gambut, demikian luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para pengusaha dan kelompok masyarakat mampu lainnya yang tidak digarap, telah menjadikan tempat tersebut sebagai muara dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput. Prayitno dan Munandar (2016), menyatakan kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 adalah tergolong lahan sangat besar yang berdampak pada kerugian finansial, lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan yang juga merugikan masyarakat berupa gangguan kesehatan, pendidikan dan aktivitas penduduk. Luas kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan mencapai 128.314 hektar. Lahan terbakar tersebut tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir . Peta rawan kebakaran Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 5.8.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 104
Sumber: BNPB Sumsel (2016)
Gambar 5.8. Peta rawan kebakaran Propinsi Sumatera Selatan
Dampak langsung kebakaran hutan dan lahan gambut bagi manusia adalah kehilangan sumber mata pencaharian masyarakat terutama bagi mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam (berladang, beternak, berburu, menangkap ikan dan sebagainya). Ladang, perkebunan dan lahan pertanian lain yang terbakar akan memusnahkan semua tanaman, yang berarti pada akhirnya produksi pertanian akan ikut terbakar (Adinugroho dkk, 2005). Selain dampak secara ekonomi, kebakaran hutan dan lahan gambut juga berdampak pada lingkungan yang bersifat global. Salah satu dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yaitu berkurangnya unsur hara karena lapisan bumi yang semakin menipis, sedangkan keseimbangan unsur hara pada tanah lahan gambut mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia (Wildayana dan Armanto, 2009).
Kerusakan fungsi ekosistem gambut akibat kebakaran hutan berdampak pada penurunan ketersediaan air dalam tanah. Kondisi yang demikian dapat memacu kekeringan dan merubah sifat tanah gambut menjadi kering tak balik. Oleh karena itu perlu pengelolaan yang khas agar tidak terjadi perubahan karakteristik yang menyebabkan produktivitas lahan menurun, tidak produktif dan terbakar (Masganti dkk, 2014). Luas daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.8.
Upaya penumbuhan kembali dengan melakukan pemulihan fungsi lahan gambut yang berkelanjutan dilaksanakan pada satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Noor (2010) berpendapat bahwa lahan gambut bersifat rapuh artinya apabila perlakuan berlebihan tanpa memperdulikan kaidah-kaidah konservasi dan reservasi maka sifat biogeokimia dan watak bawaan lahan gambut akan berubah dan rusak. Kebakaran di lahan gambut merupakan cerminan dari sistem pengelolaan hutan/lahan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 105
yang mengabaikan sifat- sifat dan watak lahan danlingkungan gambut yaitu mudah kering dan terbakar.
Konservasi hutan adalah suatu bentuk usaha melestarikan hutan yang tujuan utamanya adalah menjaga spesies tanaman dan hewan tertentu di dalamnya dari ancaman kepunahan. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui restorasi ekosistem gambut yang dinaungi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui kegiatan 3R (Rewetting, Revegetation dan Revitalitation). Kebakaran di lahan gambut yang ekstrim memerlukan perbaikan terhadap ekosistem lahan gambut secara berkelanjutan, seperti kebakaran yang terjadi pada lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan yang selalu terulang dan menjadi permasalahan serius yang harus ditangani ( Suwignyo et al., 2017b). Dengan melakukan kegiatan 3R salah satunya yaitu penanaman kembali setelah tanah gambut kembali menjadi lembab atau revegetasi diharapkan mampu menghasilkan timber produk seperti hasil hutan yang berupa produksi kayu, nilai ekologi dan lingkungan hijau yang bernilai jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat menjaga kesuburan tanah dan air. Strategi pendekatan 3R tersebut penerapannya tergantung dari target kawasan yang akan direstorasi. Dari target tersebut ada sekitar 400 ribu ha areal yang direstorasi di kawasan APL yang melibatkan masyarakat. Kawasan ini merupakan areal yang secara umum sudah dibuka dan dikelola serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Untuk kawasan ini maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem paludikultur dan agroforestry multi tanaman.
Tabel 5.6. Luas daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Sumatera Selatan
No Kabupaten Tidak Rawan
Rendah Sedang Rawan Sangat Rawan
Luasan Per Kabupaten
1 Banyuasin 295 311.212 372.484 417.964 74.174 1.176.128 2 Empat Lawang 167.473 55.330 1.379 1.915 - 226.097 3 Lahat 178.412 160.327 36.238 39.328 - 414.304 4 Lubuklinggau 3.442 30.353 914 - - 34.710 5 Muara Enim 107.180 360.778 118.183 82.219 24.795 693.154 6 Musi Banyuasin - 766.054 344.604 265.516 40.344 1.416.517 7 Musi Rawas 72.229 351.291 144.550 57.584 54 625.710 8 Musi Rawas Utara 181.405 323.316 45.966 32.424 3.591 586.703 9 Ogan Ilir - 71.273 84.061 68.954 - 224.289
10 Ogan Komering Ilir
- 319.234 249.918 642.915 475.281 1.687.348
11 Ogan Komering Ulu
83.134 168.461 80.238 32.635 - 364.468
12 Ogan Komering Ulu Selatan
159.853 154.826 100.311 1.081 - 416.070
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 106
13 Ogan Komering Ulu Timur
- 161.204 57.885 113.518 - 332.607
14 Pagar Alam 60.832 2.496 - - - 63.328 15 Palembang - 19.238 15.045 740 - 35.022
16 Penukal Abab Lematang Ilir
- 111.022 26.586 24.656 19.413 181.677
17 Prabumulih - 38.589 4.089 2.888 - 45.566
Luasan Per Tingkat Rawan
1.014.256 3.405.005 1.682.449 1.784.338 637.652 8.524.176
Sumber: BNPB Sumsel (2016)
Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan merupakan desa yang diberi bantuan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk dilaksanakan pilot project implementasi model restorasi integrasi dan paludikultur lahan gambut serta merupakan salah satu lokasi di Sumatera Selatan yang ditelusuri adanya titik api saat terjadi kebakaran ekstrim pada lahan gambut. Membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut, memang telah lumrah dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Alasannya, selain tidak mengeluarkan modal, cara seperti itu telah dilakukan turun temurun sejak nenek moyang. Selain kebiasaan masyarakat yang melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar, yang lebih parah lagi kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Kerumitan di lapangan terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN. Sehingga perlu adanya kegiatan dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut di Sumatera Selatan.
Kegiatan restorasi lahan gambut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budidaya gambut dengan tanaman pertanian, pakan ternak dan sistem pertanian yang sesuai dengan keperluan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lahan gambut yang tersisa menjadi penting untuk direstorasi secara efektif dan berkelanjutan. Kegiatan merestorasi gambut merupakan upaya yang strategis terutama untuk pengembangan komoditi ekonomis yang mendukung pendapatan masyarakat (Susanto, 2014). Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penyebab kebakaran kawasan lahan gambut dengan mempertahankan lahan gambut agar tetap berada pada kondisi basah dan lembab dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 1) Model Restorasi Gambut Terintegrasi, 2) Model Paludikultur dan Agrofrestry.
Terkait dengan restorasi gambut pada tahun 2017, Universitas Sriwijaya telah mengusung Pilot Project di kawasan Ogan Komering Ilir, yaitu :
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 107
1) Pilot Project Implementasi Model Restorasi Gambut Terintegrasi di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2) Pilot Project Implementasi Model Paludikultur dan Agroforestry di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung kerja Badan Restorasi Gambut (BRG), antara lain :
1) Pemulihan ekosistem gambut untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan a. Pengembangan dan peningkatan tata kelola restorasi gambut b. Pengembangan rencana restorasi gambut dan pengelolaan kerjasama
2) Perlindungan ekosistem gambut untuk mendukung sistem penyangga kehidupan a. Pemulihan ekosistem gambut yang teregradasi melalui konstruksi operasi
restorasi hidrologis dan vegetatif b. Peningkatan sosialissasi dan edukasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unutk mendukung pelaksanaan
restorasi gambut terintegrasi
Setelah lahan gambut direstorasi, lahan gambut akan ditanami komoditi khas gambut yang disebut dengan paludikultur. Paludikultur merupakan budidaya pada lahan basah dengan menggunakan teknik restorasi ;ahan rawa gambut dengan memulihkan kondisi lahan gambut menjadi basah kembali. Paludikultur dapat memanfaatkan tanaman semusim dengan kemampuan tumbuh yang baik pada lahan gambut seperti jelutung, gelam, purun dan nenas. Paludikultur adalah menanam vegetasi khas rawa gambut di kawasan budidaya selain mendapatkan fungsi rehabilitasi juga memiliki nilai ekonomi. Pengembangan paludikultur dapat memanfaatkan tanaman semusim dengan kemampuan tumbuh baik pada lahan gambut (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara monokultur dan polikultur. Kondisi tanah yang basah atau muka air tanah yang tinggi tetap dipertahankan tanpa pembuatan kanal, bahkan kanal-kanal yang telah ada diupayakan untuk ditutup agar gambut terairi kembali.
5.2.2. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan analisis profitabilitas dan keekonomian berbagai model paludikultur yang dikembangkan pada berbagai wilayah gambut di Provinsi Sumatera Selatan.
5.2.3. Metode Pelaksanaan a. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam dan Desa Sepucuk Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 108
bahwa di Desa Perigi dan Desa Sepucuk merupakan lokasi percontohan pengembangan model paludikultur untuk restorasi integrasi pada lahan gambut yang didanai oleh Badan Restorasi Gambut. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 hingga selesai.
b. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk kelengkapan data dalam proses penelitian serta wawancara langsung kepada petani dan stakeholder yang telah menerapkan model paludikultur.
c. Metode Penentuan Lokasi
Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive sampling), yaitu Desa Perigi dan Desa Sepucuk. Hal ini dilakukan mengingat tanaman yang ada di lokasi project di Desa Perigi belum bisa dinilai secara ekonomi. Dengan demikian, Desa Sepucuk juga dijadikan sebagai sumber data penelitian.
d. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa survei dan wawancara langsung dengan petani contoh dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner. Petani contoh adalah pihak yang relevan memberikan informasi pengembangan model paludikultur dan restorasi integrasi pada lahan gambut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan sumber-sumber serta lembaga yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.
e. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Metode yang diperoleh di lapangan diolah secara tabulasi dan uraian secara deskripstif yaitu memaparkan hasil dalam bentuk uraian yang sistematis pada pembahasan. Adapun untuk menjawab untuk melaksanakan analisis keekonomian dan profitabilitas berbagai model paludikultur digunakan Analisis Biaya dan Manfaat. Biaya total TC (total cost) didapat dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variablel total, dapat diformulasikan sebagai berikut (Akhmad, 2014):
( ) ( )
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 109
Keterangan : TC = Biaya total Invesment Cost = Biaya yang dikeluarkan sebelum proyek berproduksi Operational Cost = Biaya yang dikeluarkan setelh proyek berproduksi TVC = Biaya variabel total TFC = Biaya tetap total
Fungsi penerimaan TR (total revenue) dalam usahatani sebagai berikut:
Keterangan : Pn = penerimaan petani dalam project (Rp) Q = produksi yang dihasilkan (Kg) Hy = harga dari produk (Rp)
Untuk dapat menghitung Net Present Value (NVP) diperlukan selisih antara pendapaan dan biaya.
∑ ( )
Keterangan : Bt = manfaat pada tahun ke -1 Ct = biaya pada yahun ke -1 t = tahun kegiatan bisnis i = tingkat discount rate
NPV dapat juga disebut sebagai akumulasi discount rate present value (PV) dari keuntungan bersih atau jumlah nilai sekarang keuntungan bersih yang dihasilkan dari tahun proyek berjalan.
( )
Untuk mengetahui besarnya IRR, maka diadakan percobaan-percobaan dengan menggunakan beberapa tingkat discount rate yang berbeda sehingga menghasilkan NPV yang mendekati nol. Jika hasil percobaan menunjukkan nilai NPV negative, berarti tingkat discount rate (i) terlalu tinggi, sehingga di waktu yang akan datang nilai benefit (keuntungan) terlalu b) lebih berat, Karena menyebabkan PV Biaya (Cost) lebih besar dari pada PV Benefit (Keuntungan). Jika hasil percobaan menghasilkan nilai NPV positif, hal ini berarti nilai tingkat discount rate (i) terlalu rendah, sehingga di waktu yang akan datang benefit terlalu berat untuk disamakan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 110
dengan PV biaya. Kemudian hasil percobaan dimasukan ke dalam rumus IRR sebagai berikut :
( )
Keterangan : i1 = discount rate yang menghasilkan NPV positif i2 = discount rate yang menghasilkan NPV negativ NPV1 = nilai NPV positif NPV2 = nilai NPV negatif
Net Benefit Cost Rasio Adalah perbandingan manfaat dan biaya dengan rumus sebagai berikut :
( )
( )
⁄
Keterangan : Bt = manfaat pada tahun ke -1 Ct = biaya pada yahun ke -1 t = tahun kegiatan bisnis i = tingkat discount rate
Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan/produksi. Analisa yang juga dikenal dengan isti-lah CPV (Cost-Profit-Volume) ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat terse-but perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian.
Analisa BEP dihitung dengan formula sebagai berikut:
atau dapat juga dituliskan sebagai:
|
|
Analisis sensitivitas suatu proyek pada dasarnya menghadapi ketidakpastian
karena dipengaruhi perubahan-perubahan, baik dari sisi pengeluaran yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat kelayakan suatu proyek. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasakan perlu untuk dilakukan sebuah analisis atau penelaahan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 111
kembali terhadap suatu proyek untuk melihat pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat adanya perubahan-perubahan tersebut (Gittinger, 1986) dalam Purnomo (2008). Analisis Sensitivitas merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sebuah analisis atau penelaahan kembali terhadap suatu proyek untuk melihat pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat adanya kondisi yang berubah-ubah atau ketidakpastian. Dalam analisis kelayakan agribisnis, analisis sensitivitas dilakukan pada arus penerimaan (inflow) dan arus pengeluaran (outflow), yaitu perubahan pada harga output, tingkat produksi, harga input dan tingkat suku bunga.
5.2.4. Hasil Analisis 5.2.4.1. Gambaran Umum Budidaya Tanaman Paludikultur
1) Gambaran Umum Budidaya Tanaman Jelutung
Jelutung rawa dapat dikembangkan dengan pola Perhutanan Sosial (hutan rakyat, hutan kemasyarakatan), HTI, campuran dengan kelapa sawit, atau tumpangsari dengan tanaman pertanian dan kolam (Agrosilvofishery) untuk memperoleh hasil getah, kayu dan pemulihan fungsi lingkungan suatu wilayah (Bastoni, 2014). Budidaya tanaman jelutung di lahan gambut mulai dari pembibitan, persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan serta perlindungan. Jelutung Rawa (Dyera lowii) sesuai ditanam pada lahan rawa gambut dan lahan rawa bergambut, seperti di : - Kawasan hutan produksi bekas tebangan & kebakaran - Zona penyanggah kawasan konservasi - Areal konservasi, pohon kehidupandanpohon unggulan pada HTI rawa - Lahan usaha transmigrasi daerah rawa yang kurang sesuai untuk tanaman pangan
dan lahan rawa tidak produktif milik masyarakat.
a. Pembibitan Jelutung
Penyapihan bibit dilakukan pada persemaian permanen atau semi permanen yang dinaungi paranet dengan intensitas naungan 50 –75 persen. Polibag yang dapat digunakan untuk penyapihan bibit berukuran 15 cm x 10cm atau lebih besar tergantung lama waktu pindah tanam (transplanting) ke lapangan. Kriteria bibit siap tanam: tinggi minimal 25 cm, diameter minimal 0,5 cm, jumlah daun minimal 8 helai, batang lurus, perakaran sudah menyatu dengan media. Umur bibit siap tanam tergantung dari cara pembibitannya. Pada pembibitan manual (tanpa genangan) bibit siap tanam 8 –10 bulan setelah sapih. Pembibitan dengan teknik genangan buatan setinggi 30% dari tinggi polibag, bibit siap tanam 4 –6 bulan setelah sapih dan konsumsi air 28 kali lebih hemat daripada pembibitan manual.
b. Penyiapan Lahan Jelutung
Jelutung rawa termasuk jenis pohon yang membutuhkan cahaya penuh untuk pertumbuhannya dan jenis ini cocok ditanam pada hutan rawa gambut yang terbuka, seperti areal bekas tebangan dan kebakaran. Pada areal terbuka bekas kebakaran,
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 112
penyiapan lahan dilakukan dengan sistem jalur, lebar jalur 1,0–2,0 m dan jarak antar jalur 5 m, jarak tanam yang dapat digunakan 5mx 5 m, 5 m x 4 m, atau 5 m x 3 m. Setelah pembuatan jalur dilakukan pemasangan ajir dan pembuatan gundukan gambut, khusus untuk lahan gambut yang belum didrainase. Tujuannya untuk mengumpulkan massa tanah sebagaitempat berjangkarnya perakaran tanaman dan meninggikan bagian tanah agar bibit tidak terendam air. Tinggi gundukan minimal 50% dari tinggi genangan air pada puncak musim hujan.Pembuatan gundukan pada lahan rawa gambut disajikan pada Gambar 9. Pada areal terbuka bekas tebangan, untuk tanaman pengayaan, penyiapan lahan dilakukan dengan sistem jalur, lebar jalur 1-2m dan jarak antar jalur 10 m, jarak tanam 10m x 5m.
c. Penanaman dan Pemeliharaan
Sebelum penanaman, bibit diadaptasikan di tempat terbuka selama 1 bulan dengan cara pembukaan paranet di persemaian.Penanaman dilakukan pada awal musim hujan (Oktober-November) sebelum genangan air rawa tinggi, dan tinggi bibit perlu disesuaikan dengan tinggi genangan air. Tinggi bibit minimal sepertiga lebih tinggi dari genangan air pada puncak musim hujan. Pemeliharaan tanaman dilakukan minimal sampai umur 3 tahun, berupa pembebasan tumbuhan bawah dan pemupukan.Pada tahun pertama pembebasan tumbuhan bawah dilakukan minimal 3 kali. Pada tahun kedua dan ketiga pembebasan tumbuhan bawah dilakukan masing-masing 2 kali. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali pada awal dan akhir musim hujan sampai tanaman berumur 3 tahun. Pupuk yang digunakan NPK tablet dengan dosis 20 -30 gram (2 –3 tablet) per tanaman setiap periode pemupukan.
d. Penyadapan Getah Jelutung
Pohon jelutung rawa dapat mulai disadap getahnya jika diameter pohon berukuran > 15 cm. Dengan riap diameter 2,0 –2,5 cm/tahun maka pada umur pohon 6 –7 tahun, pohon jelutung dapat mulai disadap. Makin besar ukuran diameter pohon akan makin baik karena getah yang dihasilkan akan lebih banyak dan kerusakan pohon akan dapat diminimalkan.
e. Pemanenan Kayu Jelutung
Kayu Jelutung dapat dipanen pada saat usia tanaman 30 tahun. Kayu jelutung dapat digunakan untuk kayu pertukangan.
2) Gambaran Budidaya Tanaman Meranti
Meranti merupakan salah satu kayu komersial yang sudah banyak dikenal oleh berbagai negara Asia Tenggara dengan berbagai nama perdagangan, terutama jenis meranti merah (Shorea spp). Meranti merah termasuk jenis endemik di Indonesia di antaranya yang terancam punah yaitu S. Leprosula (Kalimantan), S. Ovalis
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 113
(Kalimantan) dan S. selanica (Maluku) yang masuk ke dalam daftar merah IUCN (Ashton 2011).
a. Penyapihan dan Pembibitan
Apabila benih meranti yang disemai telah berkecambah dan memiliki dua pasang daun, maka siap disapih. Penyapihan bibit dapat dilakukan dengan memindahkan bibit dari bedeng semai atau bak semai ke kantong plastik. Bibit dipelihara di persemaian hingga mencapai tinggi 30-50 cm, atau kurang lebih 2-3 bulan. Setelah itu, bibit siap ditanam di lapangan.
b. Penanaman
Bibit meranti ditanam pada musim hujan. Tahap-tahap penanamannya adalah sebagai berikut: Buat lubang tanam berukuran 30cm x 30cm x 20cm, mengikuti ajir. Lepaskan kantong plastik dengan hati-hati agar tidak merusak perakaran. Tanam bibit ke dalam lubang tanam, dan timbun dengan tanah kembali. Setiap lubang ditanami dengan satu bibit meranti.
c. Pemeliharaan
Pemeliharaan meranti dilakukan sampai sebelum tanaman akan dipanen kayunya yaitu minimal 10 tahun. Pada tahun pertama pembebasan tumbuhan bawah dilakukan minimal 3 kali. Pada tahun kedua hingga tahun sebelum panen kayu, pembebasan tumbuhan bawah dilakukan masing-masing 2 kali. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali pada awal dan akhir musim hujan sampai tanaman berumur 3 tahun. Pupuk yang digunakan NPK, Urea dan Dolomit.
d. Panen Kayu
Pemanenan kayu atau penebangan kayu meranti dapat dilakukan ketika umur tanaman sudah 10 tahun, ada juga yang menebang kayunya ketika umur 15 tahun. Penjarangan kayu meranti dilakukan ketika umur 8 tahun. Dengan perkiraan diameter tumbuh 2,82 cm per tahun dan tinggi 131cm per tahun.
3) Gambaran Budidaya Tanaman Nanas
Prospek pengembangan nanas cukup besar, terutama setelah Hawaii yang selama ini dikenal sebagai produsen nanas kalengan mulai mengalihkan perhatiannya keindustri pariwisata. Peluang ini mulai ditangkap oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Permintaan pasar dalam negeri terhadap buah nanas cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, makin baiknya pendapatan masyarakat. Tanaman nanas dapat tumbuh dan beradaptasi baik didaerah tropis yang terletak antara 25° Lintang Utara sampai 25° Lintang Selatan dengan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 114
ketinggian tempat100 m–800 m dari permukaan laut dan temperatur antara 21°C –27°C. Tanaman akan berhenti tumbuh bila temperatur terletak antara 10° C –16°C. Bila temperatur di atas 37°C, maka tanaman akan mengalami luka-luka karena transpirasi dan respirasi yang berlebihan (Hadiati dan Indriyani, 2008 ).
Tanaman nanas membutuhkan tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik, sehingga sesuai ditanam di lahan gambut. Disamping itu, tanaman nanas juga membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun dengan suhu optimum 32°C (Rukmana, 1996; Nurhayati, 2014). Tanaman nanas sangat toleran terhadap tingkat keasaman tanah yang cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman hortikultura lain. Pada tanah pH 3,0 nanas tumbuh dan berproduksi dengan baik, padahal tanaman lain pasti mendapat gangguan pertumbuhan dan hasil(Litbangtan).Kondisi tersebut menjadikan nanas sebagai salah satu tanaman hortikultura yang sangat cocok dibudidayakan pada areal lahan gambut yang umumnya bersifat sangat asam atau ph rendah. Bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa nanas yang dibudidayakan pada lahan gambut relatif lebih manis rasa buahnya dibandingkan nanas yang dibudidayakan pada lahan non gambut.
a. Pembibitan
Keberhasilan penanaman nanas sangat ditentukan oleh kualitas bibit. Nanas dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif dan generatif. Cara vegetatif digunakan adalah tunas akar, tunas batang, tunas buah, mahkota buah dan stek batang. Cara generatif dengan biji yang ditumbuhkan dengan persemaian, (jarang digunakan). Kualitas bibit yang baik harus berasal dari tanaman yang pertumbuhannya normal, sehat serta bebas dari hama dan penyakit. Pemeliharaan pembibitan/persemaian penyiraman dilakukan secara berkala dijaga agar kondisi media tanam selalu lembab dan tidak kering supaya bibit tidak mati. Pemupukan dilakukan dengan pemberian pupuk kandang dengan perbandingan kadar yang sudah ditentukan. Penjarangan dan pemberian pestisida dapat dilakukan jika diperlukan. Pemindahan bibit dapat dilakukan jika ukuran tinggi bibit mencapai 25-30 cm atau berumur 3-5 bulan.
b. Persiapan Lahan
Penanaman nanas dapat dilakukan pada lahan tegalan atau ladang. Waktu persiapan dan pembukaan lahan yangpaling baik adalah disaat waktu musim kemarau, dengan membuang pepohonan yang tidak diperlukan. Pengolahan tanah dapat dilakukan pada awal musim hujan. Derajat keasaman tanah perlu diperhatikan karena tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik pada pH sekitar 5,5. Jumlah bibit yang diperlukan untuk suatu lahan tergantung dari jenis nanas, tingkat kesuburan tanah dan ekologi pertumbuhannya.
c. Penanaman
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 115
Penanaman yang baik dilakukan pada awal musim hujan. Langkah-langkah yang dilakukan: (1) membuat lubang tanam sesuai dengan jarak dan sistem tanam yang dipilih; (2) mengambil bibit nanas sehat dan baik dan menanam bibit pada lubang tanam yang tersedia masing-masing satu bibit per lubang tanam; (3) tanah ditekan/dipadatkan di sekitar pangkal batang bibit nanas agar tidak mudahroboh dan akar tanaman dapat kontak langsung dengan air tanah; (4) dilakukan penyiraman hingga tanah lembab dan basah; (5) penanaman bibit nanas jangan terlalu dalam, 3-5 cm bagian pangkal batang tertimbun tanah agar bibit mudah busuk.
d. Pemeliharaan
Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur 2-3 bulan dengan pupuk buatan. Pemupukan susulan berikutnya diulang tiap 3-4 bulan sekali sampai tanaman berbunga dan berbuah. Sekalipun tanaman nanas tahan terhadap iklim kering, namun untuk pertumbuhan tanaman yang optimal diperlukan air yan cukup. Pengairan /penyiraman dilakukan 1-2 kali dalam seminggu atau tergantung keadaan cuaca. Tanaman nanas dewasa masih perlu pengairan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan secara optimal. Pengairan dilakukan 2 minggu sekali. Tanah yang terlalu kering dapat menyebabkan pertumbuhan nanas kerdil dan buahnya kecil-kecil. Waktu pengairan yang paling baik adalah sore dan pagi hari dengan menggunakan mesin penyemprot atau embrat.
e. Panen
Panen buah nanas dilakukan setelah nanas berumur 12-24 bulan, tergantung dari jenis bibit yang digunakan. Bibit yang berasal dari mahkota bunga berbuah pada umur 24 bulan, hingga panen buah setelah berumur 24 bulan. Tanaman yang berasal dari tunas batang dipanen setelah umur 18 bulan, sedangkan tunas akar setelah berumur 12 bulan. Ciri-ciri buah nanas yang siap dipanen:
- Mahkota buah terbuka. - Tangkai ubah mengkerut. - Mata buah lebih mendatar, besar dan bentuknya bulat. - Warna bagian dasar buah kuning. - Timbul aroma nanas yang harum dan khas.
4) Gambaran Budidaya Cabe
Tanaman cabai merupakan salah satu sayuran buah yang memiliki peluang bisnis yang baik. Besarnya kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri menjadikan cabai sebagai komoditas menjanjikan. Permintaan cabai yang tinggi untuk kebutuhan bumbu masakan, industri makanan, dan obat-obatan merupakan potensi untuk meraup keuntungan. Tidak heran jika cabai merupakan komoditas hortikultura yang mengalami fluktuasi harga paling tinggi di Indonesia. Harga cabaiyang tinggi
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 116
memberikan keuntungan yang tinggi pula bagi petani. Keuntungan yang diperoleh dari budidaya cabai umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya sayuran lain. Cabai pun kini mnejadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Namun, banyak kendala yang dihadapi petani dalam berbudidaya cabai. Salah satunya adalah hama dan penyakit seperti kutu kebul, antraknosa, dan busuk buah yang menyebabkan gagal panen. Selain itu, produktivitas buah yang rendah dan waktu panen yang lama tentunya akan memperkecil rasio keuntungan petani cabai. Menurut Rizqi (2010), teknik budidaya cabe terdiri dari :
a. Pengadaan Benih
Pengadaan benih dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri atau membeli benih yang telah siap tanam. Pengadaan benih dengan cara menbeli akan lebih praktis, petani tinggal menggunakan tanpa jerih payah. Sedangkan pengadaan benih dengan cara membuat sendiri cukup rumit. Di samping itu, mutunya belum tentu terjamin baik. Keberhasilan produksi cabai merah sangat dipengaruhi oleh kualitas benih yang dapat dicerminkan oleh tingginya produksi, ketahanan terhadap hama dan penyakit serta tingkat adaptasi iklim. Biji benih lebih baik membeli dari distributor atau kios yang sudah dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kemurnian dan daya kecambahnya.
b. Persiapan Lahan
Sebelum menanam cabai, hendaknya tanah digaap terebuh dahulu, agar tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar sehingga pertukaran udara dalam tanah membaik oksigen dapat masuk kedalam tanah, gas yang dapat meracuni akar tanaman akan teroksidasi dan asam-asam dapat keluar dari tanah. Melonggarkan tanah akan memberikan ruang bagi akar untuk bebas menyerap zat-zat makanan di dalamnya.
c. Penanaman
Bibit cabai dipersemaian yang telah berumur 15–17 hari atau telah memiliki 3 atau 4 daun, siap dipindah tanam pada lahan. Semprot bibit dengan fungisida dan insektisida 1–3 hari sebelum dipindahtanamkan untuk mencegah serangan penyakit jamur dan hama sesaat setelah pindah tanam. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari atau pada saat cuaca tidak terlalu panas, dengan cara merobek kantong semai dan diusahakan media tidak pecah dan langsung dimasukkan pada lubang tanam (Dermawan, 2010).
d. Pemeliharaan
Bibit atau tanaman yang mati harus disulam atau diganti dengan sisa bibit yang ada. Penyulaman dilakukan pagi atau sore hari, sebaiknya minggu pertama dan minggu kedua setelah tanam. Semua jenis tumbuhan pengganggu (gulma)
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 117
disingkirkan dari lahan bedengan tanah yang tidak tertutup mulsa. Tanah yang terkikis air atau longsor dari bedeng dinaikkan kembali, dilakukan pembubunan (penimbunan kembali). Pemupukan diberikan 10-14 hari sekali. Pupuk daun yang sesuai misalnya Complesal special tonic. Untuk bunga dan buah dapat diberikan pupuk kemiral red pada umur 35 HST. Kegiatan pengairan atau penyiraman dilakukan pada saat musim kering. Penyiraman dengan kocoran diterapakn jika tanaman sudah kuat. Sistem terbaik dengan melakukan penggenangan dua minggu sekali sehingga air dapat meresap ke perakaran.
e. Panen dan Pasca Panen
Pemanenan tanaman cabai menurut adalah pada saat tanaman cabai berumur 75 – 85 hst yang ditandai dengan buahnya yang padat dan warna merah menyala, buah cabai siap dilakukan pemanenan pertama. Umur panen cabai tergantung varietas yang digunakan, lokasi penanaman dan kombinasi pemupukan yang digunakan serta kesehatan tanaman. Tanaman cabai dapat dipanen setiap 2 – 5 hari sekali tergantung dari luas penanaman dan kondisi pasar.
Pemanenan dilakukan dengan cara memetik buah beserta tangkainya yang bertujuan agar cabai dapat disimpan lebih lama. Buah cabai yang rusak akibat hama atau penyakit harus tetap di panen agar tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman cabai sehat. Pisahkan buah cabai yang rusak dari buah cabai yang sehat. Waktu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena bobot buah dalam keadaan optimal akibat penimbunan zat pada malam hari dan belum terjadi penguapan.
Penanganan pasca panen tanaman cabai adalah hasil panen yang telah dipisahkan antara cabai yang sehat dan yang rusak, selanjutnya dikumpulkan di tempat yang sejuk atau teduh sehingga cabai tetap segar .Untuk mendapatkan harga yang lebih baik, hasil panen dikelompokkan berdasarkan standar kualitas permintaan pasar seperti untuk supermarket, pasar lokal maupun pasar eksport. Setelah buah cabai dikelompokkan berdasarkan kelasnya, maka pengemasan perlu dilakukan untuk melindungi buah cabai dari kerusakan selama dalam pengangkutan. Kemasan dapat dibuat dari berbagai bahan dengan memberikan ventilasi. Cabai siap didistribusikan ke konsumen yang membutuhkan cabai segar.
5.2.4.2. Pengembangan Model Paludikultur di Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan
Kebakaran hebat yang terjadi pada lahan gambut pada tahun 2015 berdampak tidak hanya pada unsur hara tanah gambut, tetapi juga sosial ekonomi masyarakat sekitar. Akibat dari El Nino, tanah harus di restorasi agar dapat ditanami kembali tanaman yang mampu hidup di tanah gambut. Dampak kebakaran hutan dan lahan menyebabkan asap yang memberikan kerugian ekonomi yang dapat mencapai
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 118
milyaran rupiah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran bisa merupakan unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Masyarakat biasanya membuka lahan dengan cara membakarnya, dengan alasan karena sudah menjadi tradisi dan tidak memerlukan biaya besar yang seharusnya dikurangi untuk mencegah terjadinya kebakaran besar pada lahan gambut lain. Apalagi jika ada konflik warga dan perusahaan tertentu, warga menggunakan api untuk menjarah lahan tanpa pemilik. Unsur ketidaksengajaan juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran lahan, misalnya membuang puntung rokok dalam keadaan kamarau yang akan memicu terjadinya kebakaran dengan cepat yang sulit untuk dikendalikan.
Kebakaran hutan dan lahan juga disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain kondisi iklim, kondisi fisik lahan, dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar. Kondisi iklim yang kering dan panas menjadi pemicu kebakaran. Kebakaran rawan terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kebakaran akan semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Kebakaran akan berkurang jika telah masuk musim penghujan dimana intensitas panas akan menurun. Kondisi fisik lahan dan hutan yang telah terdegradasi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran. Makin berkurangnya lahan gambut di Ogan Komering Ilir akibat kebakaran tak hanya memberikan kerugian bagi kehidupan manusia saja, tetapi berimbas pula pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Jika kebakaran terus saja terjadi kedepannya, tentunya lahan gambut akan semakin banyak hilang, ekosistem makin tak seimbang lalu bumi akan semakin tercemar. Keberlangsungan lahan gambut semakin dipertanyakan.
Usaha-usaha untuk menjaga lahan gambut saat ini telah banyak dilakukan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan gambut dari degradasi yang makin parah, yakni dengan mencetuskan moratorium gambut. Moratorium ini berisi kebijakan tentang penudaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produk yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain untuk digunakan dalam sektor perkebunan. Akan tetapi moratorium ini tidak berlaku untuk perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada selama izin di bidang usaha tersebut masih berlaku.
Dalam rangka konservasi lahan gambut, Badan Restorasi Gambut menyusun program 3R yaitu reweeting, revegetasi, dan revitalisasi penghidupan masyakarat. Tentu saja program ini harus didukung dengan penyusunan berbagai aktifitas dan kegiatan di dalamnya. Banyak hasil riset yang menyajikan bahwa terdapat berbagai model untuk pengembangan aktifitas dan kegiatan konservasi gambut. Salah satunya adalah paludikultur.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015), menyatakan pengembangan Paludikultur dapat memanfaatkan tanaman semusim dengan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 119
kemampuan tumbuh baik pada lahan gambut, antara lain tanaman nanas dan lidah buaya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan secara monokultur dan atau polikultur. Pada sistem monokultur, lahan gambut hanya ditanami tanaman nanas. Sedangkan dengan sistem polikultur nanas ditanam campur dengan tanaman lain, penanamannya tersusun dan terencana dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik.
Beberapa keuntungan dari sistem tumpangsari antara lain pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok, peningkatan produksi total persatuan luas karena lebih efektif dalam penggunaan cahaya, air serta unsur hara, disamping dapat mengurangi resiko kegagalan panen dan menekan pertumbuhan gulma, dan pada akhirnya ekosistem yang terbentuk menjadi lebih komplek dan lebih tahan terhadap perubahan faktor luar. Tanaman nanas merupakan tanaman paling tahan di lahan masam. Tanaman nanas dapat tumbuh pada tanah pH 3,0 dengan pertumbuhan tanaman dan berproduksi dengan baik (Stanturf et al., 2012). Jenis tanaman nanas madu kemudian banyak ditanam di tanah gambut di Jambi, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia (Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, 2013).
Agroforestri adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan serta peningkatan produktivitas lahan. Masalah yang sering timbul ialah alih fungsi lahan yang menyebabkan lahan hutan semakin berkurang. Teknik Agroforestri merupakan pola kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian yang dilaksanakan di lahan hutan zona budidaya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Pengelolaan lahan gambut dengan tanaman tahunan, akan memberikan nilai ekonomis yang lebih apabila ditumpangsarikan dengan tanaman pangan dan hortikultura musiman. Hal ini menjadi titik tolak pemikiran pembangunan pilot project penelitian di semua lokasi. Selain menerapkan teknologi untuk menurunkan emisi GRK dari tanah gambut, di setiap pilot project tanaman tahunan, ditumpangsarikan dengan tanaman semusim (pangan, hortikultura) yang mempunyai nilai ekonomis. Metode ini diberi nama Paludikultur.
1) Gambaran Umum
Keberhasilan melakukan restorasi lahan gambut melalui sistem paludikultur melalui pola agroforestry dengan sistem tumpang sari juga sudah dilakukan oleh Bastoni dan Tim Balai Litbang LKH Palembang di wilayah Sepucuk Kabupaten OKI. Berdasarkan keberhasilan ini ada beberapa tanaman kehutanan yang dapat direkomendasikan yaitu Jelutung, Meranti, Ramin, Punak sedangkan untuk tanaman budidaya dapat digunakan tanaman Nenas, Jagung, Lengkuas, Kunyit, singkong, pisang (Bastoni dan Tim Peneliti Balai Litbang LKH Palembang, 2017).
Menurut Erizal et al., (2017) dan Rujito et al., (2017) mengembangkan model paludikultur dan Resorasi integrasi di Desa Perigi Kecamatan Pangkalam Kabupaten
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 120
OKI. Jenis tanaman kehutanan yang dipilih adalah dari jenis tanamman lokal (Indigeneous Species) yaitu Jelutung (Dyera lowii), Meranti Bunga (Shorea leprosula) dan Meranti Batu (Shorea platyclados), serta Tanaman Sagu (Metroxylon rumphii), Gelam (Melaleuca spp) Tanaman sela yang akan digunakan adalah Tanaman Nanas. Tanaman Nanas menjadi pilihan untuk pengembangan tanaman sela mengingat hampir sebagian besar perkebunan kelapa sawit di wilayah Sepucuk Kota Kayu Agung, menggunakan nanas sebagai tanaman sela. Pemilihan komodi kehutanan dan hortikultira yang dikembangkan juga didasarkan pada hasil riset Harun, 2013; Bastoni, 2014; Daisuke et al., 2013; dan Karyanto, 2015. Hasil riset tahun 2017 tersebut menunjukan bahwa Dari sekian banyak jenis tanaman yang ditanam, nampak bahwa sekitar 40 % tanaman Sagu mengalami kematian. Pemotongan tunas ini tujuannya untuk memudahkan pengangkutan. Sementara untuk tanaman kehutanan yang lain relatif tumbuh dan diharapkan akan hidup. Ada beberapa tanaman yang mati dan memerlukan penyulaman, tetapi jumlahnya relatif tidak banyak, berkisar 10 – 20 % saja. Tanaman meranti dan jelutung adalah tanaman yang memiliki daya adaptasi paling baik, karena tingkat kematiannya hanya berkisan 5-10 %. Untuk melihat perbandingan pertumbuhan tanaman hutan lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 5.7.
Tabel. 5.7. Perbandingan Pertumbuhan Beberapa Tanaman Hutan Gambut
No. Tanaman Persentase
Pertumbuhan (%)
Peningkatan tinggi tanaman
(cm/tahun)
Peningkatan diameter batang (cm/tahun)
1 Jelutung 91 214 2,83 2 Meranti 95 131 2,82
Dapat dilihat dari Tabel 5.7 di atas, pertumbuhan tanaman jelutung lebih cepat dibandingkan dengan tanaman lain. Jika dilihat waktu tanamnya, jelutung sudah ditanam sejak 8 tahun lalu. Dan berdasarkan fakta di lapangan, getah jelutung sudah bisa untuk disadap dan kayunya sudah bisa ditebang untuk dijual dengan tinggi batang mencapai lebih dari 1.700 cm. Sama seperti jelutung, ramin juga di tanam di waktu yang sama akan tetapi pertumbuhannya dibawah jelutung. Berdasarkan fakta di lapangan, diameter tanaman ramin masih kecil. Begitu juga dengan tanaman punak, diameter batangnya masih kecik tapi tinggi batang diperkirakan sudah mencapai lebih dari 760cm. Tanaman meranti memiliki sifat khusus yaitu mampu hidup tanpa drainase, jadi pertumbuhannya cukup subur meskipun baru berumur 6 tahun. Dengan demikian, tanaman kehutanan yang memiliki daya tahan di lahan gambut adalah Jelutung dan Meranti.
Beberapa tanaman sela hortikultura ditanam di lahan gambut seperti nenas, kopi, laos dan kunyit. Hasil analisis di lapangan menunjukkan tidak semua tanaman hortikultura memiliki pertumbuhan yang baik di lahan gambut. Hasil pengamatan terhadap 4 lokasi paludikultur yang diteliti, terdapat beberapa tanaman yang tahan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 121
untuk dikembangkan di lahan gambut. Di 4 lokasi yang diteliti, telah ditanami beberapa tanaman yaitu nanas, terong, cabe, jagung, kangkung, cabe, tomat dan padi. Dari beberapa tanaman yang telah dikembangkan tersebut, tampak secara ekologi tanaman cabe dan nanas memiliki pertumbuhan paling baik dan juga memiliki pasar yang luas. Kedua tanaman ini juga terbukti relatif tahan terhadap rendaman.
2) Pola Pembiayaan
Pola pembiayaan pengembangan model paludikultur di Kabupaten OKI umumnya berasal dari bantuan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang bekerjasama dengan pihak lain, diantarnya dengan Perguruan tinggi, Badan Restorasi Gambut, dan juga lembaga non pemerintah. Pada tahun-tahun berikutnya, pengembangan model paludikultur ini dapat dilakukan dengan modal sendiri yang diperoleh dari keuntungan penjualan-penjualan hasil produksi pertanian sebelumnya.
Selanjutnya untuk pengembangan model paludikultur ke depan, selain dari modal yang diberikan di awal, petani dapat memanfaatkan dana kredit dari bank dengan proporsi yang beragam tergantung skala usaha. Adapun beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit dari bank adalah : (1). Surat pengajuan kredit dari debitur, (2).Pengumpulan data (data keuangan, jaminan), (3).Pembuatan proposal, dan (4).Pengajuan ke komite kredit.
Beberapa persyaratan lain adalah semua transaksi keuangan dilakukan melalui rekening di bank yang bersangkutan. Biaya administrasi yang ditanggung oleh calon debitur adalah provisi sebesar 1%, biaya administrasi sebesar 1% (permil), biaya pengikatan jaminan, biaya notaris dan biaya resiko. Kriteria yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis kredit kepada nasabah adalah 5C, yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (permodalan), collateral (jaminan) dan condition (kondisi).
Selain lembaga perkreditan formal tersebut, sumber pembiayaan yang juga diakses oleh petani adalah lembaga perkreditan non formal yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau tetangga wilayah sentra usaha. Sistem perkreditan ini lebih sederhana, tanpa syarat-syarat dan agunan tertentu, hanya didasarkan pada faktor kepercayaan antara pemilik uang dan nasabahnya. Besarnya pinjaman berkisar antara Rp 1,000.000,00 – Rp 5.000.000,00.
3) Aspek Pemasaran
Salah satu aspek yang perlu menjadi pertimbangan untuk pengembangan model usaha paludikultur ini adalah tersedianya pasar untuk berbagai produk pertanian yang dihasilkan. Selama ini, sebagai petani, metode pemasaran produk pertanian yang dihasilkan masih bersifat sederhana dan konvensional yaitu dengan cara menunggu calon pembeli/pedagang pengumpul datang ke lokasi. Dengan sistem pemasaran
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 122
tersebut, maka kegiatan pemasaran produk menjadi tidak efisien dan tidak banyak memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi petani. Untuk itu, dalam pengembangan model usaha paludikultur ini, maka sistem saluran pemasaran harus diperbaiki supaya efisien dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: a. Pengaktiftan peran kelompok tani. Hasil riset menunjukkan bahwa cukup banyak
kelompok tani yang tidak aktif di wilayah OKI. Hal ini terjadi karena (1) Keterbatasan jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Cakupan kerja 1 orang PPL adalah 1 kecamatan. Tentu saja hal ini menyebabkan produktifitas PPL rendah, dan (2) Pengetahuan PPL yang terbatas, biasanya hanya mengenai tanaman pangan, ternak dan ikan saja. Tidak banyak PPL yang memahami tentang tanaman perkebunan. Oleh karenanya, untuk mendukung keberhasilan program ini, maka perlu dilakukan peningkatan produktifitas PPL melalui (1) mekanisme pemberian insentif, (2) pelatihan secara rutin, dan (3) penambahan jumlah PPL perkebunan.
b. Pembentukan koperasi usaha petani. Hasil riset menunjukkan koperasi tidak banyak ditemukan di beberapa wilayah pertanian lahan gambut di Kabupaten OKI. Ketidakberadaan koperasi menyebabkan menjadi hanya sebagai price taker di pasar produk. Koperasi akan membantu petani dari sisi pemasaran dengan cara menemukan pasar yang tepat dengan petani. Dengan membentuk koperasi, maka petani memiliki posisi tawar di pasar produk.
c. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk perbaikan proses pasca panen, perluasan pasar dan pemasaran. Dengan demikian, petani akan mendapat peningkatan pendapatan dari kegiatan ini.
Dalam rangka pengembangan model paludikultur, salah satu hal yang penting menjadi pertimbangan bahwa model paludikultur memiliki dua bantuk produk yang akan dipasarkan yaitu : (1) Hasil Hutan Kayu, dan (2) Hasil Hutan non Kayu (produk hortikultura). Pengembangan pasar harus diarahkan untuk 2 produk tersebut dengan cara: (1) Untuk memasarkan Hasil Hutan Kayu, petani melalui kelompok tani dan koperasi perlu melakukan kerjasama dengan perusahaan industri pulp dan pertukangan, dan (2) untuk memasarkan Hasil Hutan non Kayu (produk hortikultura) maka petani melalui kelompok tani dan koperasi perlu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, rumah makan, dan pengusaha produk retail untuk memperluas pemasaran. Dua langkah ini dipandang perlu untuk mendukung kontinuitas pasar dan pemasaran.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penjualan getah jelutung. Saat ini getah jelutung kehilangan pasar di dalam negeri. Oleh karenanya, dalam pengembangan model paludikultur jelutung, perlu dibarengi dengan penciptaan pasar getah jelutung dan juga proses pengolahan getah jelutung menjadi produk setengah jadi.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 123
4) Harga Produk hasil Komoditi Harga produk kehutanan sangat bervariasi. Untuk produk hasil hutan, terdapat
berbagai tingkat harga tergantung pada diameter kayu yang dihasilkan. Dapat dilihat pada Tabel 5.8. Tabel 5.8. Harga Produk Hasil Hutan Kayu
Hasil Hutan Kayu
No. Jenis Tanaman Jenis Produk Kualifikasi Produk Harga
1. Meranti Kayu Meranti Volume 2-3 m3 Rp 400.000/btg
2. Jelutung Kayu Jelutung Diameter 40 cm, tinggi 12 m, dan Volume 0,84 m3
Rp 450.000/m3
Untuk produk bukan hasil hutan, terdapat berbagai tingkat harga tergantung pada kualifikasi produk. Dapat dilihat pada Tabel 5.9. Tabel 5.9. Harga Produk Hasil Hutan Bukan Kayu
Hasil Hutan Bukan Kayu
No. Jenis
Tanaman Jenis
Produk Kualifikasi Produk Harga
1. Jelutung Getah Jelutung
Tk.Penyadap Tk. Pengumpul Tk. Pengusaha
Rp 3.500/Kg Rp 5.000/Kg
Rp 15.000/Kg 2. Nanas Panen 1
Panen 2 Panen 2
Ukuran besar Ukuran sedang Ukuran kecil
Rp 5.000/buah Rp 4.000/buah Rp 3.000/buah
3. Cabe Cabe Cabe Keriting Rp 15.000/kg
5) Gambaran Lokasi Pilot Project
Wilayah kabupaten OKI memiliki potensi lahan gambut yang sangat besar.sehingga selama ini pengembangan model paludikultur ini sangat potensial dikembangkan di wilayah ini. Selama tahun 2017 dan 2018, Universitas Sriwijaya dan BP2LHK Palembang telah mengembangkan beberapa demplot di Kabupaten OKI. Lokasi tersebut antara lain: a. Universitas Sriwijaya membangun 2 demplot di Desa Perigi, Kecamatan
Pangkalan Lampan, Kabupaten OKI (Gambar 5.9) b. BP2LHK Palembang membangun 3 demplot di DesaSepucuk, Kecamatan Kayu
Agung, Kabupaten OKI dan 1 Demplot di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampan, Kabupaten OKI (Gambar 5.10).
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 124
(Sumber: Rujitoet al., 2017)
Gambar 5.9. Lokasi Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampan, Kabupaten OKI
a. b. c. d. e. f.
(Sumber: Bastoni, 2017)
Gambar 5.10. Lokasi Desa Sepucuk, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI
Semua demplot dibangun berbasis masyarakat, sehingga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, analisis kelayakan ekonomi dan profitabilitas ini disusun berdasarkan kondisi di lokasi demplot yang dibangun tersebut.
a. Fasilitas Produksi
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 125
Seperti halnya proses produksi pertanian dan perkebunan pada umumnya, maka proses produksi dilakukan secara alami dan manual dengan mengandalkan kondisi alam dan kemampuan/keterampilan petani. Kondisi alam dibutuhkan dalam menentukan proses pengolahan, pembersihan, penanamam, pemupukan, penyiangan dan pemananen, sedangkan keterampilan mutlak diperlukan karena keseluruhan proses produksi tersebut. Untuk kegiatan di atas, fasilitas produksi yang diperlukan antara cangkul, parang, pemotong rumput, handspayer, dan chainsaw.
b. Bibit dan Benih
Bibit meranti, jelutung, nanas, serta benih tanaman diperoleh dari petani, balai penelitian, dan juga toko pertanian. Pasokan bibit tanaman kehutanan cukup banyak tersedia di pasaran, begitu juga untuk benih tanaman hortikultura. Metode pembelian dapat dilakukan secara langsung atau online.
c. Tenaga Kerja
Sistem ketenagakerjaan yang digunakan dalam model ini adalah system kerja harian. Pekerja dibayar perhari sebesar Rp 60.000 untuk 6 jam kerja penuh. Tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar yang dapat dipakai untuk kegiatan. Dalam perhitungan, tenaga kerja yang dhitung adalah tenaga kerja luar keluarga.
d. Teknologi
Pada kegiatan ini diintroduksikan perlakuan biostimulan untuk tahan cekaman (Biofitalik, paten IDP000035097, FP Unsri) dan pupuk majemuk untuk tanaman yang dicobakan khususnya untuk nanas dan cabe.
e. Proses Produksi
Proses produksi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kegiatan mulai dari pengolahan sampai dengan pemanenan akhir. Untuk melaksanakan proses atau kegiatan tersebut diperlukan satu rangkaian proses pengerjaan yang bertahap. Perancangan proses produksi dalam hal ini akan tergantung pada karakteristik produk yang dihasilkan dan pola kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proyek pembuatan produk.
Implementasi model paludikultur diKabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan berbasis 3R (Rewetting, Revegetation, dan Revitalitation).
1. Rewetting: restorasi hidrologi yang dilaksanakan dengan memperbaiki tata air ekosistem gambut yang ada di lokasi. Proses rewetting melalui perbaikan kanal dan canal blocking berperan penting dalam mencegah pengeringan gambut dan pengurangan nutrien karbon (Jaenicke et al., 2010; Shiodera et al., 2016). Kegiatan ini dilakukan melalui beberapatahap:
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 126
i. Penyekatan eksisting kanal. ii. Pembuatan saluran baru dalam petakan lahan untuk pengaturan drainase. iii. Perbaikan tata air mikro dalampetakan-petakan.
2. Revegetation: restorasi berperan penting untuk mitigasi hilangnya biodiversitas gambut dan musnahnya fungsi gambut (Simila et al., 2014). Pengembangan paludikultur dilakukan untuk lahan rumah tanga petanu dengan luasan 1 hektar. Tanaman kehutanan yang dipilih adalah meranti dan jelutung. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembalikan vegetasi di lokasi restorasiadalah: a. Menyusun beberapa alternatif pola vegetasi untuk kegiatan model paludikultur b. Menentukan pola paludikulturterpilih dengan diskusi secara bersama-sama
denganmasyarakat. c. Melakukan pengolahan dan pembersihan lahan d. Melakukan Pembuatan lubang tanam e. Melakukan proses Penanaman Tanaman kehutanan Utama dengan jarak tanam 8
x 3 meter. f. Melakukan pemupukan dasar dan pemupukan lanjutan g. Melakukan pemeliharaan dalam bentuk kegiatan penyiangan, pengendelaian
hama dan penyakit, serta penyulaman 3. Revitalization: Restorasi manusia dengan mengembalikan fungsi masyarakat dalam
mengelola gambut melalui keterlibatan masyarakat desa gambut secara aktif dalam kegiatan restorasi. Kegiatan ini dilakukan juga dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan kepadamasyarakat. a. Pendekatan dan diskusi dengan kelompok masyarakat tentang potensi kegiatan
yang dapat mendukung peningkatan ekonomi/ pendapatan masyarakat. b. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi
yang telah ada.
Dalam model yang dibangun, akan dikembangkan revitalisasi pendapatan dengan pengembangan pendapatan rumah tangga melalui skenario penciptaan pendapatan bulanan bagi rumah tangga. Penciptaan pendapatan dilakukan dengan menanam tanaman hortikultura di sela-sela tanaman kehutanan yang ditanam. Tanaman yang dipilih antara lain nanas dan cabe.
f. Kendala Produksi
Kendala produksi yang dihadapi oleh petani adalah adanya konflik lahan. Konflik lahan juga seringkali terjadi antara masyarakat lokal setempat dengan perusahaan sejenis HTI yang lahannya saling berdekatan. Sementara kepastian kepemilikan lahan adalah hal yang mutlak dalam pengembangan paludikutlur, mengingat umur ekonomi proyek yang panjang.
Kondisi iklim, kondisi fisik lahan, dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar juga mempengaruhi keberhasilan pengembangan model paludikultur. Kondisi iklim
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 127
yang kering dan panas menjadi pemicu kegagalan tanam. Kegagalan tanam terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kegagalan tanam akan semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Kegagalan tanam akan berkurang jika telah masuk musim penghujan dimana intensitas panas akan menurun.
Tenaga kerja yang sedikit juga merupakan kendala dalam pengembangan model paludikultur. Saat ini, petani seringkali kesulitan menperoleh tenaga kerja dari luar keluar.Kaum muda di wilayah OKI mulai tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian. Selain itu, perkembangan perkebunan karet dan sawit yang pesat juga menjadi salah satu yang menjadi kendala untuk pengembangan model paludikultur ini.
Resiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Perubahan yang terjadi di pasar akan dipengaruhi oleh kondisi permintaaan maupun penawaran. Jika jumlah barang yang ditawarkan melimpah maka secara otomatis harga menjadi anjlok sedangkan secara global pasar akan dipengaruhi secara signifikan oleh dinamikan produksi internasional. Selain itu perubahan harga yang dihadapi oleh pelaku pertanian akan mempengaruhi minat dan kesediaan mereka untuk memproduksi suatu jenis komoditi. Kalau di kaitkan dengan produk yang dihasilkan dari tanaman meranti dan jelutung, resiko pasar tidak akan menjadi masalah bagi petani jika hasil produksi adalah kayu, sebab selain kebutuhan akan kayu yang selalu meningkat dari tahun-ketahun, kualitas meranti dan jelutung pun akan mampu bersaing dengan hasil hutan yang lain.
Selain itu pasar dari produk kayu meranti dan jelutung bukan saja berskala nasional tetapi juga internasional. Nantinya kayu meranti dan jelutung akan di distribusikan dan bekerjasama dengan perusahaan HTI atau pulp paper yang membutuhkan kayu untuk menghasilkan kertas dan tisu. Maka petani diarahkan membentuk kelompok tani yang nantinya bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai penyuluh untuk membuka koperasi sebagai sarana distribusi hasil hutan. Sedangkan untuk pasar getah jelutung sekarang sudah sulit ditemukan sehingga sebaiknya petani dan pemerintah melakukan kerjasama untuk membuka pasar atau industri pengolah getah jelutung untuk pasca panen dengan mengolah getah menjadi barang jadi karena getah jelutung hampir sama dengan getah karet pada umumnya. Ketika tanaman sedang dalam masa pertumbuhan, pasar untuk getah jelutung sudah dipersiapkan.
6) Design Pengembangan Model Paludikultur
Berdasarkan penelitian ini, jarak tanam meranti atau jelutung di asumsikan 8m x 3m sedangkan untuk tanaman sela nanas dan cabe dengan jarak tanam 1m x 1m dimana lahan seluas 10.000 m atau 1 ha dikelilingi dengan parit/kanal. Serta gambar pengaturan jarak tanam untuk pola campuran tanaman hutan dengan tanaman sela.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 128
Tanaman sel yang dipakai yaitu nanas dan cabe. Untuk melihat bentuk gambaran lahan pengembangan model paludikultur, maka dibuatlah design yang dapat dilihat pada Gambar 5.11.
g. Gambar 8. Kerangka Pengembangan Model Paludikultur di Kawasan Gambut
Gambar 5.11. Bentuk Gambaran Lahan Pengembangan Model Paludikultur
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 129
Gambar 5.12. Pengaturan Jarak Tanam Model Paludikultur Jelutung dengan Tanaman Sela (Nanas, Cabe)
Gambar 5.13. Pengaturan Jarak Tanam Model Paludikultur Meranti dengan tanaman Sela (Nanas, Cabe)
5.2.4.3. Aspek Finansial Model Tanaman Paludikultur
Dalam analisis finansial suatu usaha atau budidaya tanaman, beberapa aspek yang dihitung antara lain : biaya produksi, penerimaan dan pendapatan, NPV, IRR, BC ratio. Dalam penelitian ini, lahan yang digunakan seluas 4 hektar dengan pengembangan 4 model paludikultur yaitu Meranti-Nanas, Meranti-Cabe, Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe dengan masing-masing pembagian lahan sebesar 1 hektar.
1) Model Paludikultur Meranti – Nanas dan Meranti – Cabe Skala 1 Hektar
Pada model paludikultur campuran dalam pilot project, tanaman meranti di campur dengan nanas dan cabe dengan luash lahan yang digunakan seluas 1 ha. Meranti di campurkan dengan nanas seluas 1 ha dan meranti dicampurkan dengan cabe seluas 1 ha.
a. Asumsi Pengembangan Model
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 130
Perhitungan aspek finansial untuk model paludikultur ini menggunakan asumsi seperti dijasikan dalam Tabel 5.10. dan 5.11.
Tabel 5.10. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludikultur Meranti-Nanas Tahun 2018
No Asumsi Satuan Jumlah/Nilai Keterangan 1 Periode proyek tahun 10 2 Produksi dan Harga a. Kayu Meranti Penjarangan M3 64 Pemanenan M3 159
b. Nanas
Panen 1 7161 Panen2 6445 Panen3 5800 3 Harga a. Kayu Meranti
Penjarangan Rp/M3 400,000 Pemanenan Rp/M3 400,000 b. Nanas
Panen 1 Rp/Kg 6,000 Panen2 Panen3 4 Biaya Tenaga Kerja HOK/Hari 60,000 5 Kebutuhan bahan baku Jumlah Bahan Baku a. Bibit Meranti Buah 423 b. Bibit Nanas Buah 8,235 Harga Bahan Baku a. Bibit Meranti Rp/Buah 8,000 b. Bibit Nanas Rp/Buah 250 6 Kebutuhan Bahan penolong Jumlah Bahan Penolong a. Herbisida Round Up Liter/Ha 4 b.Biofungsisida Liter/Ha 2 d. Dolomit Kg/Ha 100 e. Urea Kg/Ha 150 f. NPK Kg/Ha 50
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 131
7 Harga Bahan Penolong a. Herbisida Rp/liter 100,000 b. Biofungsisida Rp/liter 110,000 d. Dolomit Rp/Kg 6,000 e. Urea Rp/Kg 15,000 f. NPK Rp/Kg 11,000 8 Discount Factor/suku bunga % 6 9 Luas Lahan M2 10,000 Luas kanal M2 1,164 Luas Lahan Meranti M2 8,836
10 Jarak Tanam Meranti Jarak Tanam Meranti meter 3 x 8 Jarak Tanam Nanas meter 1 x 1
11 Jumlah Tanaman M2 1,164 Meranti Pohon 368 Nanas Pohon 5,170
Berdasarkan Tabel 5.10, periode proyek mengikuti masa daur tanaman meranti
yaitu 10 tahun. Produksi kayu meranti penjarangan di asumsikan 30 persen dari jumlah panen yaitu 64 m3 dan 159 m3 saat akhir daur atau pemanenan kayu. Sedangkkan nanas, pemanenan dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun, panen ke-1 produksi di asumsikan sebanyak 7.161 kg/ha, panen ke-2 produksi diasumsikan sebanyak 6.445 kg/ha dan produksi ke-3 di asumsikan sebanyak 5.800 kg/ha. Dengan harga jual kayu meranti dari penjarangan sebesar Rp 400.000/m3 dan harga kayu meranti tebang sebesar Rp 400.000 m3 sedangkan harga jual nanas sebesar Rp 6.000/kg. Biaya tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 60.000/HOK. Pembelian bibit meranti di asumsikan sebnyak 423 bibit/ha dan bibit nanas sebnyak 8.235 bibit/ha dengan jarak tanam meranti 8 x 3 m sedangkan nanas 1 x 1 m.Untuk pemeliharaan tanaman campuran meranti-nanas, pemupukan menggunakan pupuk NPK sebnyak 50kg/ha, urea sebanyak 150kg/ha dan dolomit sebanyak 100kg/ha dan pestisida yang digunakan yaitu herbisida dan biofungisida. Jumlah tanaman meranti diasumsikan sebanyak 368 pohon/ha sedangkan nanas sebnyak 5.170 buah/ha. Discount factor diasumsuikan 6 persen dalam penelitian ini.
Tabel 5.11. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludikultur Meranti-Cabe Tahun 2018
No Asumsi Satuan Jmlh/Nilai Keterangan
1 Periode proyek tahun 10 2 Produksi dan Harga
a. Kayu Meranti
Penjarangan M3 48
Pemanenan M3 159
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 132
b. Cabe kg 2,000
3 Harga
a. Kayu Meranti
Penjarangan Rp/M3 400,000
Pemanenan Rp/M3 400,000
b. Cabe
Panen 1 Rp/Kg 17.644
4 Biaya Tenaga Kerja HOK/Hari 60,000 5 Kebutuhan bahan baku
Jumlah Bahan Baku
a. Bibit Meranti Buah 401
b. Bibit Cabe Buah 12,150
Harga Bahan Baku
a. Bibit Meranti Rp/Buah 8,000
b. Benih Cabe Paket 100
6 Kebutuhan Bahan penolong
Jumlah Bahan Penolong
a. Herbisida Liter/Ha 4
b.Biofungsisida Liter/Ha 2
d. Dolomit Kg/Ha 30
e. Pupuk Kandang Ton/Ha 5
f. NPK atau SP 36 Kg/Ha 50
g. Urea Kg/Ha 10
7 Harga Bahan Penolong
a. Herbisida Rp/liter 100,000
b.Biofungsisida Rp/liter 110,000
d. Dolomit Rp/Kg 6,000
e. Pupuk Kandang Rp/Kg 10,000
f. NPK atau SP 36 Rp/Kg 11,000
g. Urea Rp/kg 15,000
8 Peralatan
a. Tray Penyemaian Buah 243 1 tray = 50 lubang tanam; untuk 12150 tanaman
b. Ember Buah 5
c. Handsprayer Buah 1
d. Cangkul Buah 5
e. Pemotong rumput Buah 2
f. Parang Buah 5
g. Mulsa Meter 310
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 133
Harga Peralatan
a. Tray Penyemaian Rp/Buah 13.500
b. Ember Rp/Buah 10.000
c. Handsprayer Rp/Buah 350.000
d. Cangkul Rp/Buah 100.000
e. Pemotong rumput Rp/Buah 800.000
f. Parang Rp/Buah 100.000
g. Mulsa Rp/Paket 3.000
8 Discount Factor/suku bunga % 6
9 Luas Lahan M2 10,000
Luas kanal M2 1,164
Luas Lahan Meranti M2 8.836
10 Jarak Tanam Meranti
Jarak Tanam Meranti meter 3 x 8
Jarak Tanam Cabe meter 1 x 1
11 Jumlah Tanaman M2 1,164
Meranti Pohon 368
Nanas Pohon 11,045
12 Periode Tanam Cabe Bulan 6 Mei-Oktober
Berdasarkan Tabel 5.11 menunjukkan periode proyek mengikuti masa daur tanaman meranti yaitu 10 tahun. Produksi kayu meranti penjarangan di asumsikan 30 persen dari jumlah panen yaitu 48 m3 dan 159 m3 saat akhir daur atau pemanenan kayu. Sedangkkan cabe, pemanenan dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 bulan, total produksi cabe di asumsikan sebanyak 2.000kg/ha. Dengan harga jual kayu meranti dari penjarangan sebesar Rp 400.000/m3 dan harga kayu meranti tebang sebesar Rp 400.000.m3 sedangkan harga jual cabe sebesar Rp 20.000/kg. Biaya tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 60.000/HOK. Pembelian bibit meranti di asumsikan sebanyak 401 bibit/ha dan benih cabe sebnyak 12.150 benih/ha dengan jarak tanam meranti 8 x 3 m sedangkan cabe sama seperti nanas yaitu 1 x 1 m. Untuk pemeliharaan tanaman campuran meranti-cabe, sama seperti campuran Meranti-nanas, pemupukan menggunakan pupuk NPK sebnyak 50kg/ha, urea sebanyak 10kg/ha, pupuk kandang sebanyak 5kg/ha dan dolomit sebanyak 30kg/ha dan pestisida yang digunakan yaitu herbisida dan biofungisida. Jumlah tanaman meranti diasumsikan sebanyak 368 pohon/ha sedangkan nanas sebnyak 11.045 pohon/ha. Discount factor diasumsuikan 6 persen dalam penelitian ini. Karena tanaman cabe rentan dikelilingi gulma, maka guludan akan ditutupi oleh plastik mulsa seluas 310 meter.
b. Analisis Ekonomi dan Profitabilitas Meranti – Nanas dan Meranti – Cabe Skala 1 Hektar
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 134
• Biaya Investasi dan Operasional
Pada hakekatnya biaya produksi pengembangan model paludikultur terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya Investasi merupakan sejumlah uang yang digunakan pengusaha/investor usaha kerajinan purun sebagai modal awal dalam kegiatan ini. Jadi, secara umum segala bentuk modal yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan selama belum menghasilkan produk maka modal tersebut disebut investasi. Investasi ini merupakan komponen biaya tetap sesuai dengan umur ekonomisnya. Investasi usaha ditentukan selama 10 tahun. Perhitungan investasi dilakukan untuk 10 tahun dengan pertimbangan bahwa tanaman meranti siap dipanen pada usia 10 tahun sedangkan 30 tahun dengan pertimbangan bahwa tanaman jelutung siap dipanen pada usia 30 tahun. Model Paludikultur yang dikembangkan yaitu Meranti – Nanas dan Meranti – Cabe. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.12. dan Tabel 5.13.
Tabel 5.12. Biaya Investasi Model Paludikultur Campuran Meranti-Nanas Tahun 2018
No. Uraian Rotasi
Setahun Jumlah Satuan
Harga/Satuan (Rp/satuan)
Total Biaya (Rp/th)
Penyusutan (Rp/th)
1. Tenaga Kerja
51 HOK 60,000 4,980,000
-Meranti
-Nanas
2. Saprodi 1
7,440,000
3. Biaya Lahan 1 1 Ha
4. Peralatan
2,950,000
5. Biaya Bibit Meranti
423 Bibit 8,000 3,385,600
6. Biaya Pondok Kerja
1 Paket 5,000,000 5,000,000
7. Pembuatan Kanal Blocking
1 2 Paket 10,000,000 20,000,000
8. Pembuatan Saluran Kanal
1 30 HOK 60,000 1,800,000
9. Pemasangan waring untuk pagar
1 40.000 meter 5,000 200,000,000
10. Kontingensi (10%)
4,894,120
Total (Rp) 50.111.169 983,333
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 135
Berdasarkan Tabel 5.12, biaya investasi model campuran Meranti – nanas dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp 4.980.000 per tahun dan jumlah yaitu sebanyak 51. Total biaya saprodi sebesar Rp 2.920.000/ tahun. Saprodi yang digunakan terdiri dari Herbisida sebanyak 4 liter dengan harga Rp 100.000 per liter, Biofungisida sebanyak 2 liter dengan harga Rp 110.000 per liter, Dolomit sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000 per kg, pupuk urea sebanyak 150 kg dengan harga Rp 15.000 per kg, pupuk kandang sebanyak 5 kg dengan harga Rp 10.000 per kg dan NPK sebanyak 50 kg dengan harga Rp11.000/kg.
Biaya pembelian peralatan dengan total sebesar Rp 2.950.000, umur ekonomis peralatan yaitu 3 tahun. Bibit yang dibeli untuk awal penanaman sebanyak 423 bibit dengan harga Rp 5.000 per bibit. Pembuatan pondok untuk tempat perirstirahatan petani yang mengurus lahan sebesar Rp 5.000.000, pembuatan kanal blocking sebanyak 2 paket dengan biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk biaya HOK petani pembuatan kanal sebesar Rp 60.000 dengan jumlah HOK sebanyak 30. Pemsangan waring untuk pagar agar hewan liat tidak memasuki kawasan lahan yang telah ditanami seluas 40.000 meter dengan biaya sebesar Rp 5.000 per meter. Dengan suku bunga per tahunnya sebesar 10 persen. Sehingga total biaya investasi untuk model campuran Meranti-Nanas sebesar Rp 50.111.169 per tahun.
Selanjutnya berdasarkan Tabel 5.13. biaya investasi model campuran Meranti – Cabe dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp 5.100.000 per tahun dan jumlah HOK sama seperti model campuran Meranti – Nanas yaitu sebanyak 73. Total biaya saprodi sebesar Rp 2.920.000/ tahun. Saprodi yang digunakan terdiri dari Herbisida sebanyak 4 liter dengan harga Rp 100.000 per liter, Biofungisida sebanyak 2 liter dengan harga Rp 110.000 per liter, Dolomit sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000 per kg, pupuk urea sebanyak 150 kg dengan harga Rp 15.000 per kg, pupuk kandang sebanyak 5 kg dengan harga Rp 10.000 per kg dan NPK sebanyak 50 kg dengan harga Rp 11.000 per kg.
Tabel 5.13. Biaya Investasi Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe Tahun 2018
No. Uraian Rotasi
1th Jmlh Satuan
Harga/Satuan (Rp)
Total Biaya (Rp/th)
Penyusutan (Rp/th)
A. Tenaga Kerja
73 HOK 60,000 5,100,000
-Meranti -Cabe
B. Bahan-bahan
2,920,000
C. Biaya Lahan 1 1 Ha 0.00 0
D. Peralatan
2,950,000
E. Biaya Bibit Meranti
401 Bibit 8,000 3,205,400
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 136
F. Biaya Pondok Kerja
1 Paket 5,000,000 5,000,000
G. Pembuatan Kanal Blocking
1 2 Paket 10,000,000 20,000,000
F. Pembuatan Saluran Kanal
1 30 HOK 60,000 1,800,000
G.
Pemasangan waring untuk pagar
1 40.000 meter 5,000 200,000,000
D. Kontingensi (10%)
3,965,540
Total
43,620,940 983,333
Total biaya pembelian peralatan dengan total sebesar Rp 2.950.000, umur
ekonomis peralatan yaitu 3 tahun. Bibit yang dibeli untuk awal penanaman sebanyak 401 bibit dengan harga Rp 5.000 per bibit. Pembuatan pondok untuk tempat peristirahatan petani yang mengurus lahan sebesar Rp 5.000.000, pembuatan kanal blocking sebanyak 2 paket dengan biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk biaya HOK petani pembuatan kanal sebesar Rp 60.000 dengan jumlah HOK sebanyak 30. Pemasangan waring untuk pagar agar hewan liat tidak memasuki kawasan lahan yang telah ditanami seluas 40.000 meter dengan biaya sebesar Rp 5.000 per meter. Dengan suku bunga per tahunnya sebesar 10 persen. Sehingga total biaya investasi untuk model campuran Meranti-Nanas sebesar Rp 43.620.940 per tahun.
Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan yang dipengaruhi oleh faktor produksi. Biaya operasional yang digunakan pada demplot paludikultur pilot project terdiri dari model Meranti-Nanas dan Meranti-Cabe . Rincian untuk biaya operasional model campuran Meranti-Nanas dapat dilihat pada Tabel 5.14.
Tabel 5.14. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Meranti-Nanas Tahun 2018
No Biaya Total
1 Pemeliharaan tahun – 1 11,358,787
2 Pemeliharaan tahun 2 – 9 14,618,787
3 Pemeliharaan tahun – 10 13,160,000
Total 39,137,575
Berdasarkan Tabel 5.14. model paludikultur campuran Meranti-Nanas dilakukan pemeliharaan hingga masa daur tanaman. Dimana pada pemeliharaan tanaman meranti pada tahun pertama dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali, pemberian pestisida sebanyak 2 kali, penyiangan sebanyak 2 kalu dan penyulaman selama kurun waktu satu tahun jika ada tanaman yang mati. Sedangkan nanas hanya dilkukan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 137
penyulaman pada tahun pertama. Bibit tahun pertama bibit nanas ditanam sebanyak 8.235 bibit. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Meranti-Nanas tahun 1 sebesar Rp 11.358.787.
Pemeliharaan pada tahun 2 – 9 tanaman meranti dilakukan pemupukan, pemberian pestisida dan penyiangan masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu setahun. Untuk tanaman nanas, lahan untuk ditanami nanas dibersihkan dan dibuat guludan serta membuat ajir sebagai media tanam nanas. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Meranti-Nanas tahun 2-9 sebesar Rp 14.618.787. Pemeliharaan tahun 10 tanmaan meranti, tetap diberikan pupuk dan pestisida serta dilakukan penyiangan terhadap tanaman meranti masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali hingga kayu sipa untuk dipanen dan diangkut untuk dijual ke pengepul. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Meranti-Nanas tahun 10 sebesar Rp 13.160.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Meranti-Nanas sebesar Rp 39.137.575 selama 10 tahun atau rata-rata Rp 3.913.757,5 per tahun.
Tabel 5.15. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe Tahun 2018
No Biaya Total
1 Pemeliharaan tahun – 1 11,946,050.00
2 Pemeliharaan tahun 2-9 9,134,950.00
3 Pemeliharaan tahun – 10 12,000,000.00
Total 33,081,000
Berdasarkan Tabel 5.15, model paludikultur campuran Meranti-Cabe dilakukan pemeliharaan hingga masa daur tanaman meranti. Dimana pemelihraan pada tahun 1 sama seperti model sebelumnya dimana pada pemeliharaan tanaman meranti pada tahun pertama dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali, pemberian pestisida sebanyak 2 kali, penyiangan sebanyak 2 kalu dan penyulaman selama kurun waktu satu tahun jika ada tanaman yang mati. Sedangkan penanaman cabe, tahun 1 dibuat guludan dan ajir sebagai media tanam cabe. Agar cabe tidak di kelilingi gulma, maka guludan ditutupi dengan mulsa sebanyak 310 meter. serta dilakukan penyulaman jika ada bibit cabe yang mati. Benih cabe yang ditanam sebanyak 12.150 benih. Biaya yang dikelurkan pada tahun 1 sebesar Rp 11.946.050. Pemeliharaan ahun 2-9 sama seperti tahun sebelumnya, tanaman meranti dilakukan pemupukan, pemberian pestisida dan penyiangan masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu setahun. Untuk cabe, pemanenan sudah bisa dilakukann pada tahun ke 2 sebnyak 3 kali dalam rotasi satu tahun. Biaya yang dikelurkan pada tahun sebesar Rp 9.134.950.Pemeliharaan tahun 10, tetap diberikan pupuk dan pestisida serta dilakukan penyiangan terhadap tanaman meranti masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 138
hingga kayu sipa untuk dipanen dan diangkut untuk dijual ke pengepul. Biaya yang dikelurkan pada tahun 10 sebesar Rp 12.000.000. Sehingga total biaya pemeliharaan camuran Meranti-Cabe dalam kurun waktu 10 tahun sebesar Rp 33.081.000 atau rata-rata Rp 3.308.100 per tahun.
• Perkiraan Produksi dan Penerimaan
Penerimaan yang diperoleh dari demplot paludikutur Meranti-Nanas dan Meranti-Cabe dapat dilihat pada Tabel 5.16.
Tabel 5.16. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran Meranti-Nanas Tahun 2018
Komponen Harga Jual
(Rp/kg) Jumlah Total (Rp/thn)
Produksi Kayu Meranti - Penjarangan Rp 400.000 64 m3 - Pemanenan Rp 400.000 159 m3 Nanas Rp 6.000 17.466 kg Penerimaan Penerimaan Kayu Meranti Rp 89.126.531 Penerimaan Nanas Rp 53.621.568
Berdasarkan Tabel 5.16, sebelum kayu meranti ditebang terlebih dahulu dilakukan penjarangan sebesar 30 persen dari jumlah kayu yang akan dipanen yaitu 64m3 dengan harga jual kayu penjarangan Rp 400.000/ m3 sedangkan pada saat pemanenan kayu, masa akhir daur meranti tahun ke 10 sebesar 159 m3 denga harga jual kayu Rp 400.000/ m3. Sedangkan produksi nanas hingga tahun ke 10 sebesar dengan asumsu 90 persen nanas dapat dipanen dari jumlah total keseluruhan tanaman yaitu 17.466 kg dengan harga jual nanas Rp 6.000/kg. Sehingga total penerimaan kayu meranti sebesar Rp 89.126.531/ m3, sedangkan total penerimaan nanas sebesar Rp 53.621.568 selama 10 tahun atau Rp 5.362.156,8/ tahun.
Tabel 5.17. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe Tahun 2018
Komponen Harga Jual
(Rp/kg) Jumlah/satuan/tahun Total
Produksi Kayu Meranti - Penjarangan Rp 400.000 48 m3 - Pemanenan Rp 400.000 159 m3 Cabe Rp 20.000 2.000 kg Penerimaan
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 139
Penerimaan Kayu Meranti Rp 82.829.986 Penerimaan Cabe Rp 40.000.000
Berdasarkan Tabel 5.17, sebelum kayu meranti di tebang terlebih dahulu dilakukan penjarangan sebesar 48 m3 dengan harga jual kayu Rp 400.000/ m3 sedangkan pada saat pemanenan kayu, masa akhir daur meranti tahun ke 10 sebesar 159 m3 denga harga jual kayu Rp 400.000/ m3. Sedangkan produksi cabe sebanyak 2000 kg dengan harga jual Rp 20.000/ kg. Sehingga total penerimaan kayu meranti sebesar Rp 82.829.986/ m3, sedangkan total penerimaan cabe sebesar Rp 40.000.000 selama 10 tahun atau p 4.000.000/ tahun.
• Hasil Analisis Ekonomi dan Profitabilitas
Pada analisis kelayakan ekonomi, semua elemen kegiatan fsktor produksi diatas dimasukkan kedalam perhitungan cash flow, sehingga didapat benefit bersih. Dasar perhitungan dilakukan mulai dari tahun -0 dengan discount factor 6 persen. Discount factor diperlukan untuk menggambarkan proyeksi nilai nominal arus kas pada tahun-tahun selanjutnya ke nomilal saat ini ( present value). Luas lahan pilot project dalam penelitian ini seluas 4 ha dengan pembagian per model paludikultur campuran masing-masing 1 ha. Rincian arus kas model paludikultur campuran meranti nanas dan meranti-cabe dapat dilihat pada Tabel 5.18. dan 5.19.
Tabel 5.18. Analisis Finansial Model Paludikultur campuran Meranti-Nanas Tahun 2018
Komponen Jumlah Total Produksi Kayu Meranti - Penjarangan 64 m3 - Pemanenan 159 m3 Nanas 17.466 kg Penerimaan Kayu Meranti Rp 89.126.531 Penerimaan Nanas Rp 53.621.568 Pendapatan Rp 56.849.292 NPV Rp 264.290.684 IRR 74,37% PP 2,1 Gross BC 2,69 Net BC 6,25
Tabel 5.19 lebih lanjut menjelaskan bahwa, sebelum kayu meranti di tebang terlebih dahulu dilakukan penjarangan sebesar 30 persen dari jumlah kayu yang akan dipanen yaitu 64m3 dengan harga jual kayu penjarangan Rp 400.000/ m3 sedangkan pada saat pemanenan kayu, masa akhir daur meranti tahun ke 10 sebesar 159 m3
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 140
dengan harga jual kayu Rp 400.000/ m3. Sedangkan produksi nanas hingga tahun ke 10 sebesar dengan asumsu 90 persen nanas dapat dipanen dari jumlah total keseluruhan tanaman yaitu 17.466 kg dengan harga jual nanas Rp 6.000/kg.
Sehingga total penerimaan kayu meranti dalam skala 1ha sebesar Rp 89.126.531
ketika diameter pohon sudah mencapai 28,2 cm/ 10 tahun sedangkan tinggi pohon sudah mencapai 1.310 cm. Total penerimaan nanas dalam skala 1 ha yang dicampurkan dengan meranti sebesar Rp 53.621.568 mengikuti masa daur meranti hingga tahun ke 10. Sehingga rata-rata pendapatan yang diterima selama 10 tahun sebesar Rp 56.849.292. Nilai NPV pada kelayakan ekonomi model paludikultur campuran Meranti-Nanas bernilai positif menunjukkan pengembangan model paludikultur Meranti-Nanas memberikan keuntungan, nilai IRR sebesar 74,37% lebih besar dari discount factor yang dipakai dalam penelitian yaitu 6 % artinya pengembangan paludikultur Meranti-Nanas akan memberikan pendapatan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan jika tingkat suku bunga sebesar 74,37%, nilai Net BC sebesar 6,25 jika nilai Net BC > 1 maka usaha tersebut menguntungkan.
Selanjutnya berdasarkan Tabel 5.19, perkiraan produksi kayu meranti dengan skala 1 hektar mampu menghasilkan kayu 48 m3 dengan harga jual kayu hasil penjarangan sebesar Rp 400.000/m3 sedangkan kayu tebang 159m3 dengan harga jual kayu Rp 400.000/m3. Produksi cabe yang dicampur dengan tanaman jelutung mampu menghasilkan 2.000 kg/ha/thn dengan harga jual Rp 20.000/kg. Tabel 5.19. Analisis Finansial Model Paludikultur campuran Meranti-Cabe Tahun
2018
Komponen Jumlah Total Produksi Kayu Meranti - Penjarangan 48 m3 - Pemanenan 159 m3 Cabe 2.000 kg Penerimaan Kayu Meranti Rp 82.829.986 Penerimaan Cabe Rp 40.000.000 Pendapatan Rp 43.893.635 NPV Rp 209.459.294 IRR 64,67% PP 2,3 Gross BC 2,85 Net BC 5,63
Sehingga total penerimaan kayu meranti dalam skala 1 ha sebesar Rp 625.342.211 ketika diameter pohon sudah mencapai 28,2 cm/ 10 tahun sedangkan tinggi pohon sudah mencapai 1.310 cm. Total penerimaan cabe dalam skala 1 ha yang dicampurkan dengan meranti sebesar Rp 40.000.000 mengikuti masa daur meranti
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 141
hingga tahun ke 10. Sehingga rata-rata pendapatan yang diterima selama 10 tahun sebesar Rp 43.893.635. Nilai NPV pada kelayakan ekonomi model paludikultur campuran Meranti-Cabe bernilai positif menunjukkan pengembangan model paludikultur Meranti-Cabe memberikan keuntungan, niai IRR sebesar 64,67% lebih besar dari discount factor yang dipakai dalam penelitian yaitu 6 % artinya pengembangan paludikultur Meranti-Cabe akan memberikan pendapatan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan jika tingkat suku bunga sebesar 64,67%, nilai Net BC yaitu 5,63 jika nilai Net BC > 1 maka usaha tersebut menguntungkan.
2) Model Paludikultur Campuran Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe Skala 1 Hektar
a. Asumsi Pengembangan Model
Perhitungan aspek finansial untuk model paludikultur Campuran Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe Skala 1 Hektar menggunakan asumsi seperti dijadikan dalam Tabel 5.20.
Tabel 5.20. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludikultur Jelutung-Nanas Tahun 2018
No Asumsi Satuan Jumlah/Nilai Keterangan
1 Periode proyek tahun 30 2 Produksi dan Harga
a. Kayu Jelutung
Pemanenan M3 159
b. Nanas
Panen 1 7.161
Panen2 6.445
Panen3 5.800
c. Getah Jelutung
Pemanenan kg/tahun 13,248
8 hingga 12 tahun = 3kg
kg/tahun 22,080
13 hingga 30 tahun = 5 kg
3 Harga
a. Kayu Jelutung Rp/Kg 30,000
b. Getah Jelutung Rp/kg 6,000
c. Nanas Rp/kg 6,000
4 Biaya Tenaga Kerja HOK/Hari 60,000
Pemupukan HOK/Hari 60,000
Penyadapan dan pengolahan HOK/Hari 65,000
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 142
getah
5 Kebutuhan bahan baku
Jumlah Bahan Baku
a. Bibit Jelutung Buah 423
b. Bibit Nanas Buah 8,235
Harga Bahan Baku
a. Bibit Jelutung Rp/Buah 8,000
b. Bibit Nanas Rp/Buah 250
6 Kebutuhan Bahan penolong
Jumlah Bahan Penolong
a. Herbisida Round Up Liter/Ha 4
b.Biofungsisida Liter/Ha 2
c. Asam fosfat Liter/Ha 201.6
d. Dolomit Kg/Ha 100
e. Urea Kg/Ha 150
f. NPK Kg/Ha 50
7 Harga Bahan Penolong
a. Herbisida Rp/liter 100,000
b. Biofungsisida Rp/liter 110,000
c. Asam fosfat Rp/liter 60,000
d. Dolomit Rp/Kg 6,000
e. Urea Rp/Kg 15,000
f. NPK Rp/Kg 11,000
8 Discount Factor/suku bunga % 6 9 Luas Lahan M2 10,000.00
Luas kanal M2 1,164
Luas Lahan Jelutung M2 8,836
10 Jarak Tanam Meranti
Jarak Tanam Jelutung meter 3 x 8
Jarak Tanam Nanas meter 1 x 1
11 Jumlah Tanaman M2 1,164
Jelutung Pohon 368
Nanas Pohon 7,161
Berdasarkan Tabel 5.20, periode proyek mengikuti masa daur tanaman meranti yaitu 30 tahun. Produksi kayu jelutung di asumsikan 159 m3 saat akhir daur atau pemanenan kayu, getah jelutung dapat dipanen setelah berumur 8 tahun dengan asumsi ketika umur 8-12 tahun produksi getah sebanyak 3kg/bulan/pohon dan umur 13-30 tahun diasumsikan produski getah sebanyak 5kg/bulan/pohon berdasarkan penelitian Karyono (2008) dalam Kristiadi (2014). Sedangkkan nanas, pemanenan dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun, panen ke-1 produksi di
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 143
asumsikan sebanyak 7.161 kg/ha, panen ke-2 produksi diasumsikan sebanyak 6.445 kg/ha dan produksi ke-3 di asumsikan sebanyak 5.800 kg/ha. Dengan harga jual kayu jelutung tanpa penjarangan sebesar Rp450.000/ m3 dan harga getah jelutung Rp 6.000/kg sedangkan harga jual nanas sebesar Rp 6.000/kg sma seperti asumsi model lainnya.. Biaya tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 60.000/HOK. Pembelian bibit jelutung di asumsikan sebnyak 423 bibit/ha dan bibit nanas sebnyak 8.235 bibit/ha dengan jarak tanam meranti 8 x 3 m sedangkan nanas 1 x 1 m. Untuk pemeliharaan tanaman campuran jelutung-nanas, pemupukan menggunakan pupuk NPK sebnyak 50kg/ha, urea sebanyak 150kg/ha dan dolomit sebanyak 100 kg/ha serta asam fosfat untuk tanaman jeluutng seanyak 201,6 liter/ha dan pestisida yang digunakan yaitu herbisida dan biofungisida. Jumlah tanaman jelutung diasumsikan sebanyak 368 pohon/ha sedangkan nanas sebnyak 7.161 buah/ha, panen berikutnya diasumsikan 90 persen dari panen pertama begitu juga dengan panen ke 3 diasumsikan 90 persen dari panen kedua. Discount factor diasumsuikan 6 persen dalam penelitian ini.
Tabel 5.21. Asumsi yang Digunakan dalam Analisis Finansial Model Paludikultur Jelutung-Cabe Tahun 2018
No Asumsi Satuan Jumlah/Nilai Keterangan
1 Periode proyek tahun 10 2 Produksi dan Harga
a. Jelutung
Pemanenan kayu M3 159
Pemanenan getah kg 13.248 8-12 tahun 3kg/pohon/bulan
kg 22.080 13-30 tahun 5kg/pohon/bulan
b. Cabe kg 2,000 3 Harga
a. Kayu Jelutung
Pemanenan Rp/M3 450,000
b. Cabe Rp/Kg 20,000
4 Biaya Tenaga Kerja HOK/Hari 60,000
5 Kebutuhan bahan baku
Jumlah Bahan Baku
a. Bibit Jelutung Buah 401
b. Bibit Cabe Buah 12,150
Harga Bahan Baku
a. Bibit Jelutung Rp/Buah 8,000
b. Benih Cabe Paket 100
6 Kebutuhan Bahan penolong
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 144
Jumlah Bahan Penolong
a. Herbisida Liter/Ha 4
b.Biofungsisida Liter/Ha 2
c. Asam fosfat Liter/Ha 201,6
d. Dolomit Kg/Ha 30
e. Pupuk Kandang Ton/Ha 5
f. NPK atau SP 36 Kg/Ha 50
g. Urea Kg/Ha 10
7 Harga Bahan Penolong
a. Herbisida Rp/liter 100,000
b.Biofungsisida Rp/liter 110,000
c. Asam fosfat Rp/liter 60,000
d. Dolomit Rp/Kg 6,000
e. Pupuk Kandang Rp/Kg 10,000
f. NPK atau SP 36 Rp/Kg 11,000
g. Urea Rp/kg 15,000
8 Peralatan
a. Tray Penyemaian Buah 243 1 tray = 50 lubang tanam; untuk 12150 tanaman
b. Ember Buah 5
c. Handsprayer Buah 1
d. Cangkul Buah 5
e. Pemotong rumput Buah 2
f. Parang Buah 5
g. Mulsa Meter 310
Harga Peralatan
a. Tray Penyemaian Rp/Buah 13500
b. Ember Rp/Buah 10000
c. Handsprayer Rp/Buah 350000
d. Cangkul Rp/Buah 100000
e. Pemotong rumput Rp/Buah 800000
f. Parang Rp/Buah 100000
g. Mulsa Rp/Paket 310
8 Discount Factor/suku bunga % 6 9 Luas Lahan M2 10,000.00
Luas kanal M2 1,164.00
Luas Lahan Jelutung M2 8,836.00
10 Jarak Tanam Jelutung
Jarak Tanam Jelutung meter 3 x 8
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 145
Jarak Tanam Cabe meter 1 x 1
11 Jumlah Tanaman M2 1,164.00
Meranti Pohon 368.00
12 Periode Tanam Cabe Bulan 6 Mei-Oktober
Berdasarkan Tabel 5.21, periode proyek mengikuti masa daur tanaman meranti yaitu 30 tahun. Produksi kayu jelutung di asumsikan 159 m3 saat akhir daur atau pemanenan kayu dan getah jelutung dapat dipanen setelah berumur 8 tahun dengan asumsi ketika umur 8-12 tahun produksi getah sebanyak 3kg/bulan/pohon dan umur 13-30 tahun diasumsikan produski getah sebanyak 5kg/bulan/pohon berdasarkan penelitian Karyono (2008) dalam Kristiadi (2014).. Sedangkkan cabe, pemanenan dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 bulan, total produksi cabe di asumsikan sebanyak 2.000kg/ha. Dengan harga jual kayu jelutung tanpa penjarangan sebesar Rp 450.000.m3 sedangkan harga jual cabe sebesar Rp 20.000/kg. Biaya tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 60.000/HOK. Pembelian bibit meranti di asumsikan sebanyak 401 bibit/ha dan benih cabe sebnyak 12.150 benih/ha dengan jarak tanam meranti 8 x 3 m sedangkan cabe sama seperti nanas yaitu 1 x 1 m. Untuk pemeliharaan tanaman campuran jelutung-cabe, sama seperti campuran Meranti-nanas, pemupukan menggunakan pupuk NPK sebnyak 50kg/ha, urea sebanyak 10kg/ha, pupuk kandang sebanyak 5kg/ha dan dolomit sebanyak 30kg/ha serta asam fosfat untuk tanaman jeluutng seanyak 201,6 liter/ha dan pestisida yang digunakan yaitu herbisida dan biofungisida. Jumlah tanaman meranti diasumsikan sebanyak 368 pohon/ha sedangkan nanas sebnyak 11.045 pohon/ha. Discount factor diasumsuikan 6 persen dalam penelitian ini. Karena tanaman cabe rentan dikelilingi gulma, maka guludan akan ditutupi oleh plastik mulsa seluas 310 meter.
b. Analisis Ekonomi dan Profitabilitas Jelutung – Nanas dan Jelutung – Cabe Skala 1 Hektar • Biaya Investasi dan Operasional
Pada hakekatnya biaya produksi pengembangan model paludikultur terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya Investasi merupakan sejumlah uang yang digunakan pengusaha/investor usaha kerajinan purun sebagai modal awal dalam kegiatan ini. Jadi, secara umum segala bentuk modal yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan selama belum menghasilkan produk maka modal tersebut disebut investasi. Investasi ini merupakan komponen biaya tetap sesuai dengan umur ekonomisnya. Investasi usaha ditentukan selama 10 tahun. Perhitungan investasi dilakukan untuk 10 tahun dengan pertimbangan bahwa tanaman meranti siap dipanen pada usia 10 tahun sedangkan 30 tahun dengan pertimbangan bahwa tanaman jelutung siap dipanen pada usia 30 tahun. Model Paludikultur yang dikembangkan yaitu Meranti – Nanas dan Meranti – Cabe. Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.22 dan Tabel 5.23.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 146
Tabel 5.22. Biaya Investasi Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas Tahun 2018
No. Uraian Rotasi
Setahun Jumlah Satuan
Harga/Satuan (Rp/satuan)
Total Biaya
(Rp/th)
1. Tenaga Kerja
51 HOK 60,000 4,980,000
Jelutung
Nanas
2. Bahan-bahan
19,536,000
3. Biaya Lahan 1 1 Ha
0
4. Peralatan
3,360,000
5. Biaya Bibit Jelutung
423 Bibit 8,000 3,385,600
6. Biaya Pondok Kerja
1 Paket 5,000,000 5,000,000
7. Pembuatan Kanal Blocking 1 2 Paket 10,000,000 20,000,000
8. Pembuatan Saluran Kanal 1 30 HOK 60,000 1,800,000
9. Pemasangan waring untuk pagar 1 40000 Meter 5,000 200,000,000
10. Kontingensi (10%)
5,806,160
Total 58,061,600
Berdasarkan Tabel 5.30, biaya investasi model campuran Jelutung – Nanas dengan total biaya tenaga kerja sebesar Rp 4.980.000 per tahun dan jumlah HOK sebanyak 51. Total biaya saprodi sebesar Rp 19.536.000 per tahun. Saprodi yang digunakan terdiri dari Herbisida sebanyak 4 liter dengan harga Rp 100.000 per liter, Biofungisida sebanyak 2 liter dengan harga Rp 110.000 per liter, Dolomit sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000 per kg, pupuk urea sebanyak 150 kg dengan harga Rp 15.000 per kg, Asam fosfat 201,6 liter dengan harga Rp 60.000/liter dan NPK sebanyak 50 kg dengan harga Rp 11.000 per kg. Dikarenakan lahan merupakan lahan petani, sehingga tidak ada biaya untuk penyewaan lahan. Biaya pembelian peralatan dengan total sebesar Rp 3,385,600, umur ekonomis peralatan yaitu 3 tahun. Bibit jelutung yang dibeli untuk awal penanaman sebanyak 423 bibit dengan harga Rp 8.000 per bibit. Pembuatan pondok untuk tempat perirstirahatan petani yang mengurus lahan sebesar Rp 5.000.000, pembuatan kanal blocking sebanyak 2 paket dengan biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk biaya HOK petani pembuatan kanal sebesar Rp 60.000 dengan jumlah HOK sebanyak 30. Pemsangan waring untuk pagar agar hewan liat tidak memasuki kawasan lahan yang telah ditanami seluas 40.000
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 147
meter dengan biaya sebesar Rp 5.000 per meter. Dengan suku bunga per tahunnya sebesar 10 persen. Sehingga total biaya investasi untuk model campuran Meranti-Nanas sebesar Rp 58,061,600 per 30 tahun atau rata-rata sebesar Rp 1.935.386 per tahun.
Tabel 5.23. Biaya Investasi Model Paludikultur campuran Jelutung-Cabe Tahun 2018
No. Uraian Rotasi
Setahun Jumlah Satuan
Harga/Satuan (Rp/satuan)
Total Biaya (Rp/th)
1. Tenaga Kerja
73 HOK 60,000 5,100,000
Jelutung
2. Bahan-bahan
19,636,000
3. Biaya Lahan 1 1 Ha 0 0
4. Peralatan
3,360,000
5. Biaya Bibit Jelutung
423 Bibit 8,000 3,385,600
6. Biaya Pondok Kerja
1 Paket 5,000,000 5,000,000
7. Pembuatan Kanal Blocking 1 2 Paket 10,000,000 20,000,000
8. Pembuatan Saluran Kanal 1 30 HOK 60,000 1,800,000
9. Pemasangan waring untuk pagar 1 40000 M 5,000 200,000,000
10. Kontingensi (10%)
5,828,160
Total 58,281,600
Berdasarkan Tabel 5.23, biaya investasi model campuran Jelutung – Cabe
dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp 5.100.000 per tahun dan jumlah HOK sebanyak 73. Total biaya saprodi sebesar Rp 19.636.000 / tahun. Saprodi yang digunakan terdiri dari Herbisida sebanyak 4 liter dengan harga Rp 100.000 per liter, Biofungisida sebanyak 2 liter dengan harga Rp 110.000 per liter, Dolomit sebanyak 100 kg dengan harga Rp 6.000 per kg, pupuk urea sebanyak 150 kg dengan harga Rp 15.000 per kg, Asam fosfat 201,6 liter dengan harga Rp 60.000/liter dan NPK sebanyak 50 kg dengan harga Rp 11.000 per kg. Total biaya pembelian peralatan dengan total sebesar Rp 3.360.000, umur ekonomis peralatan yaitu 3 tahun. Bibit jelutung yang dibeli untuk awal penanaman sebanyak 423 bibit dengan harga Rp 8.000 per bibit. Pembuatan pondok untuk tempat perirstirahatan petani yang mengurus lahan sebesar Rp 5.000.000, pembuatan kanal blocking sebanyak 2 paket dengan biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk biaya HOK petani pembuatan kanal sebesar Rp 60.000 dengan jumlah HOK sebanyak 30. Pemsangan waring untuk pagar agar hewan liat tidak memasuki kawasan lahan yang telah ditanami seluas 40.000 meter dengan biaya
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 148
sebesar Rp 5.000 per meter. Dengan suku bunga per tahunnya sebesar 10 persen. Sehingga total biaya investasi untuk model campuran Jelutung-Cabe sebesar Rp 58.281.600 per 30 tahun atau rata-rata sebesar Rp 1.942.720 per tahun.
Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan yang dipengaruhi oleh faktor produksi. Biaya operasional yang digunakan pada demplot paludikultur pilot project terdiri dari model Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe . Rincian untuk biaya operasional model campuran Jeluutng-Nanas dapat dilihat pada Tabel 5.24.
Tabel 5.24. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas Tahun 2018
No Biaya Total
1 Pemeliharaan tahun – 1 12,060,788
2 Pemeliharaan tahun 2-29 15,020,788
3 Pemeliharaan tahun – 30 26,042,000
Total 53,123,576
Berdasarkan Tabel 5.24, model paludikultur campuran Jelutung-Nanas dilakukan pemeliharaan hingga masa daur tanaman yaitu 30 tahun. Dimana pada pemeliharaan tanaman jelutung pada tahun pertama dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali, pemberian pestisida sebanyak 2 kali, penyiangan sebanyak 2 kalu dan penyulaman selama kurun waktu satu tahun jika ada tanaman yang mati. Sedangkan nanas hanya dilakukan penyulaman pada tahun pertama. Bibit tahun pertama bibit nanas ditanam sebanyak 8.235 bibit sma seperti model sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Jelutung-Nanas tahun 1 sebesar Rp 12.060.788. Pemeliharaan pada tahun 2 – 29 tanaman meranti dilakukan pemupukan, pemberian pestisida dan penyiangan masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu setahun. Untuk tanaman nanas, lahan untuk ditanami nanas dibersihkan dan dibuat guludan serta membuat ajir sebagai media tanam nanas. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Jelutung-Nanas tahun 2-9 sebesar Rp 15.020.788. Pemeliharaan tahun 10 tanmaan meranti, tetap diberikan pupuk dan pestisida serta dilakukan penyiangan terhadap tanaman meranti masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali hingga kayu sipa untuk dipanen dan diangkut untuk dijual ke pengepul. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Meranti-Nanas Jelutung-Nanas tahun 10 sebesar Rp 26.042.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan campuran Jelutung-Nanas sebesar Rp 53.123.576
selama 10 tahun atau Rp 5.312.357,6 per tahun.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 149
Tabel 5.25. Biaya Operasional Model Paludikultur campuran Jelutung-Cabe Tahun 2018
No Biaya Total
1 Pemeliharaan tahun - 1 13,073,000
2 Pemeliharaan tahun 2-29 15,016,950
3 Pemeliharaan tahun - 30 19,922,000
Total 48,011,950
Berdasarkan Tabel 5.25, model paludikultur campuran Jelutung-Cabe dilakukan pemeliharaan hingga masa daur tanaman meranti. Dimana pemelihraan pada tahun 1 sama seperti model sebelumnya dimana pada pemeliharaan tanaman meranti pada tahun pertama dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali, pemberian pestisida sebanyak 2 kali, penyiangan sebanyak 2 kalu dan penyulaman selama kurun waktu satu tahun jika ada tanaman yang mati. Sedangkan penanaman cabe, tahun 1 dibuat guludan dan ajir sebagai media tanam cabe. Agar cabe tidak di kelilingi gulma, maka guludan ditutupi dengan mulsa sebanyak 310 meter. serta dilakukan penyulaman jika ada bibit cabe yang mati. Benih cabe yang ditanam sebanyak 12.150 benih. Biaya yang dikelurkan pada tahun 1 sebesar Rp 11.946.050. Pemeliharaan tahun 2-9 sama seperti tahun sebelumnya, tanaman meranti dilakukan pemupukan, pemberian pestisida dan penyiangan masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu setahun. Untuk cabe, pemanenan sudah bisa dilakukann pada tahun ke 2 sebanyak 3 kali dalam rotasi satu tahun. Biaya yang dikelurkan pada tahun sebesar Rp 9.134.950.Pemeliharaan tahun 10, tetap diberikan pupuk dan pestisida serta dilakukan penyiangan terhadap tanaman meranti masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali hingga kayu sipa untuk dipanen dan diangkut untuk dijual ke pengepul. Biaya yang dikelurkan pada tahun 10 sebesar Rp 12.000.000. Sehingga total biaya pemeliharaan camuran Meranti-Cabe dalam kutun waktu 10 tahun sebesar Rp 33.111.000 atau Rp 3.311.000 per tahun.
• Analisis Ekonomi dan Profitabilitas
Penerimaan yang diperoleh dari demplot paludikutur Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe dapat dilihat pada Tabel 5.26.
Tabel 5.26. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran Jelutung-Nanas Tahun 2018
Komponen Harga Jual (Rp/kg)
Jumlah Total (Rp/thn)
Produksi Kayu Jelutung Rp 450.000 159 m3 Produksi getah Jelutung Rp 6.000
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 150
-Tahun 8-12 13.248 kg -Tahun 13-30 22.080 kg Nanas Rp 6.000 17.466 kg Penerimaan Kayu Jelutung Rp 71.550.000 Penerimaan Getah Jelutung -Tahun 8-12 Rp 79.488.000 -Tahun 13-30 Rp 132.480.000 Penerimaan Nanas Rp 53.621.568 Pendapatan Rp 143.944.421 NPV Rp 1.314.193.066 IRR 61% Net BC 21,4 Gross BC 5,75
Berdasarkan Tabel 5.26, perkiraan produksi kayu jelutung dengan skala 1 hektar mampu menghasilkan kayu 159 m3 dengan harga jual kayu Rp 450.000/m3 sedangkan produksi getah jelutung pada saat mulai panen yaitu tahun 8 hingga tahun ke 12 mempu memproduksi getah sebanyak 13.248 kg/ha/thn jika diasumsikan seluruh pohon mampu menghasilkan getah sebanyak 3 kg/bulan/pohon dari 368 pohon yang tumbuh. Pada tahun ke 13 sampai tahun 30 jelutung memproduksi getah sebanyak 22.080kg/ha/thn jika diasumsikan seluruh pohon mampu menghasilkan getah sebanyak 5kg/bulan/pohon dari 368 pohon yang tumbuh. Produksi nanas yang dicampur dengan tanaman jelutung mampu menghasilkan 16.001 kg/ha/thn dengan harga jual Rp 6.000/kg.
Sehingga total penerimaan kayu jelutung dalam skala 1ha sebesar Rp 71.550.000 ketika diameter pohon sudah mencapai 84,9 cm/ 30 tahun sedangkan tinggi pohon sudah mencapai 6.420 cm. Total penerimaan getah jelutung mulai dari tahun ke 8 sampai tahun ke 12 sebesar Rp 79.488.000 sedangkan tahun e 13 sampai tahun ke 30 penerimaan getah jelutung sebesar Rp 132.480.000. Total penerimaan nanas dalam skala 1 ha yang dicampurkan dengan meranti sebesar Rp 53.621.568 mengikuti masa daur jelutung hingga tahun ke 30. Sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh dari model Jelutung-Nanas sebesar Rp 143.944.421 selama 30 tahun. Nilai NPV pada kelayakan ekonomi model paludikultur campuran Jelutung-Nanas bernilai positif menunjukkan pengembangan model paludikultur Jeluutng-Nanas memberikan keuntungan, nilai IRR sebesar 61% lebih besar dari discount factor yang dipakai dalam penelitian yaitu 6% artinya pengembangan paludikultur Jelutung-Nanas akan memberikan pendapatan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan jika tingkat suku bunga sebesar 61%, nilai Net BC sebesar 21,4 jika nilai Net BC > 1 maka usaha tersebut menguntungkan. Tabel 5.27. Perkiraan Produksi dan Penerimaan Model Paludikultur campuran
Jelutung-Cabe Tahun 2018
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 151
Komponen Harga Jual (Rp/kg)
Jumlah Total (Rp/thn)
Produksi Kayu Jelutung Rp 450.000 159 m3 Produksi getah Jelutung Rp 6.000 -Tahun 8-12 13.248 kg -Tahun 13-30 22.080 kg Cabe Rp 20.000 2.000 kg Penerimaan Kayu Jelutung Rp 71.647.347 Penerimaan Getah Jelutung -Tahun 8-12 Rp 79.488.000 -Tahun 13-30 Rp 132.480.000 Penerimaan Cabe Rp 40.000.000 Pendapatan Rp 135.124.245 NPV Rp 1.150.825.869 IRR 48% Net BC 18,8 Gross BC 5,37
Berdasarkan Tabel 5.27, perkiraan produksi kayu jelutung dengan skala 1 hektar mampu menghasilkan kayu 159 m3 dengan harga jual kayu Rp 450.000/m3 sedangkan produksi getah jelutung pada saat mulai panen yaitu tahun 8 hingga tahun ke 12 mempu memproduksi getah sebanyak 13.248 kg/ha/thn jika diasumsikan seluruh pohon mampu menghasilkan getah sebanyak 3 kg/bulan/pohon dari 368 pohon yang tumbuh. Pada tahun ke 13 sampai tahun 30 jelutung memproduksi getah sebanyak 22.080kg/ha/thn jika diasumsikan seluruh pohon mampu menghasilkan getah sebanyak 5kg/bulan/pohon dari 368 pohon yang tumbuh. Produksi cabe yang dicampur dengan tanaman jelutung mampu mneghasilkan 2.000 kg/ha/thn dengan harga jual Rp 20.000/kg.
Sehingga total penerimaan kayu jelutung dalam skala 1ha sebesar Rp 71.647.347 ketika diameter pohon sudah mencapai 84,9 cm/ 30 tahun sedangkan tinggi pohon sudah mencapai 6.420 cm. Total penerimaan getah jelutung mulai dari tahun ke 8 sampai tahun ke 12 sebesar Rp 79.488.000 sedangkan tahun ke 13 sampai tahun ke 30 penerimaan getah jelutung sebesar Rp 132.480.000. Total penerimaan nanas dalam skala 1 ha yang dicampurkan dengan meranti sebesar Rp 40.000.000 mengikuti masa daur jelutung hingga tahun ke 30. Sehingga rata-rata pendapatan yang diperoleh dari model Jelutung-Nanas sebesar Rp 135.124.245 selama 30 tahun. Nilai NPV pada kelayakan ekonomi model paludikultur campuran Jelutung-Cabe bernilai positif menunjukkan pengembangan model paludikultur Jeluutng-Cabe memberikan keuntungan, niai IRR sebesar 48,7% lebih besar dari discount factor yang dipakai dalam penelitian yaitu 6 % artinya pengembangan paludikultur Jelutung-Cabe akan memberikan pendapatan yang sama dengan biaya yang
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 152
dikeluarkan jika tingkat suku bunga sebesar 48,7%, nilai Net BC yaitu 18,8 jika nilai Net BC > 1 maka usaha tersebut menguntungkan.
Dapat dikatakan pengembangan semua model paludikultur layak secara ekonomi, dan kegiatan pilot project ini mampu menambah penghasilan petani baik yang mempunyai lahan ataupun yang bekerja. Jika dilihat dari hasil uji kelayakan, hasil model paudikultur Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe lebih besar dari model lainnya karena selain kayu, tanaman jelutung menghasilkan getah yang bagus kualitasnya dibandingkan dengan getah karet. Selain itu, tanaman nanas juga menyokong penerimaan yang tinggi daripada cabe, dengan mencampur tanaman hutan dengan nanas maka tanah akan menjadi basah karena nanas tidak seperti tanaman sawit yang memerlukan air lebih banyak untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga berbagai manfaat dihasilkan dari pengembangan model paludikultur ini, selain mampu memberikan penghasilan kepada petani atau penduduk sekitar tetapi juga mampu mengurangi terjadinya kebakaran hutan karena tanah menjadi lembab setelah ditanami nanas.
5.2.4.4. Analisis Sensitivitas Model Tanaman Paludikultur
Kajian mengenai profitabilitas dan keekonomian model paludikultur ini juga meliputi analisis sensitivitasnya. Analisis sensitivitas pada model paludikultur ini menguji seberapa besar pengaruh perubahan dari beberapa variabel terhadap NPV, IRR dan Net BC. Kelayakan model paludikultur diuji dengan menaikkan biaya operaional dan biaya investasi; serta menurunkan harga dan produksi. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.28 sampai dengan Tabel 5.31.
Tabel 5.28. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Paludikultur Meranti-Nanas Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan
100% Rp 227.542.603 48,36% 4,08
2 Biaya Operasional dinaikkan 100%
Rp 166.622.876 48,42% 4,31
3 Harga Diturunkan 39%
Rp 530.570 6,17% 1,01
4 Produksi Diturunkan 39%
Rp 530.570 6,17% 1,01
Berdasarkan Tabel 5.28, diketahui bahwa model paludikultur meranti-nanas tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan jumlah produksi. Dari sisi biaya, meskipun biaya investasi dan biaya operasional dinaikkan hingga 100%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Selanjutnya dari sisi penerimana, jika harga jual diturunkan sampai sebesar 39%, model paludikultur
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 153
meranti-nanas masih layak secara ekonomi dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 6,17% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 1,01. Dengan nilai yang sama berlaku untuk penurunan produksi sebesar 39%. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa model paludikultur meranti-nanas lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Tabel 5.29. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Meranti-Cabe Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan
100% Rp 157.841.406 30,94% 2,74
2 Biaya Operasional dinaikkan 100%
Rp 152.597.949 46,98% 4,37
3 Harga Diturunkan 36%
Rp 2.984.089 7,07% 1,07
4 Produksi Diturunkan 36%
Rp 2.984.089 7,07% 1,07
Berdasarkan Tabel 5.29, diketahui bahwa model paludikultur meranti-cabe tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan jumlah produksi. Dari sisi biaya, meskipun biaya investasi dan biaya operasional dinaikkan hingga 100%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Selanjutnya dari sisi penerimaan, jika harga jual diturunkan sebesar 36% model paludikultur meranti-cabe masih layak secara finansial dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 7,07% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 1,07. Hasil yang sama ditunjukkan juga, jika dilakukan penurunan produksi sebesar 36%. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa model paludikultur meranti-cabe lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Tabel 5.30. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Jelutung-Nanas Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan
100% Rp 1.208.148.520 39% 12,9
2 Biaya Operasional dinaikkan 100%
Rp 1.062.278.995 40% 17,5
3 Harga Diturunkan 21%
Rp 3.361.572 6,2% 1,05
4 Produksi Diturunkan 21%
Rp 3.361.572 6,2% 1,05
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 154
Berdasarkan Tabel 5.30, diketahui bahwa model paludikultur jelutung-nanas menunjukkan hasil yang relatif sama dengan model paludikultur yang telah dibahas sebelumnya. Model ini tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan jumlah produksi. Meskipun biaya investasi dan biaya operasional dinaikkan hingga 100%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Harga jual diturunkan sebesar 21% masih layak secara finansial dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 6,2 % lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 1,05. Dengan nilai yang sama berlaku untuk penurunan produksi sebesar 21%. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa model paludikultur jelutung-nanas lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Tabel 5.31. Analisis Sensitivitas Beberapa Kemungkinan Situasi Pada Model Jelutung-Cabe Tahun 2018
No Uraian NPV IRR (%) Net BC 1 Biaya Investasi dinaikkan 100% Rp 1.109.744.076 35% 11,7
2 Biaya Operasional dinaikkan 100%
Rp 1.070.801.666 42% 17,6
3 Harga Diturunkan 19%
Rp 5.561.222 6,4% 1,08
4 Produksi Diturunkan 19%
Rp 5.561.222 6,4% 1,08
Berdasarkan Tabel 5.31, hasil analisis sensitivitas model paludikultur Jelutung-Cabe masih layak secara finansial. Meskipun biaya investasi dan biaya operasional dinaikkan hingga 100%, nilai NPV tidak menyentuh angka minus. Harga jual diturunkan sebesar 19% masih layak secara finansial dengan nilai NPV positif, nilai IRR sebesar 6,4% lebih besar dari discount factor yaitu 6% dan Net BC > 1 sebesar 1,08. Dengan nilai yang sama berlaku untuk penurunan produksi sebesar 19%. Namun, jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa model paludikultur jelutung-cabe lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 155
VI. KESIMPULAN
1. Usaha Pemeliharaan Kerbau Rawa pada lima desa Kecamatan Pampangan, yakni Desa Pulau Layang, Desa Bangsal, Desa Kuro, Desa Menggeris dan Desa Pampangan, merupakan usaha turun temurun yang dilakukan dengan sistem pola kelompok dan pola individu. Total peternak pada lima desa di Kecamatan Pampangan, yakni sebanyak 66 peternak pola kelompok dan 7 peternak pola individu. a. Total kepemilikan kerbau rawa pola kelompok pada kelima Desa di Kecamatan
Pampangan adalah 1.271 ekor dengan rata-rata jumlah anak kerbau sebanyak 3 ekor, kerbau muda sebanyak 2 ekor dan kerbau dewasa sebanyak 15 ekor. Sedangkan total kepemilikan kerbau rawa pola individu pada kelima Desa di Kecamatan Pampangan adalah 93 ekor dengan rata-rata jumlah anak kerbau sebanyak 4 ekor, kerbau muda sebanyak 2 ekor dan kerbau dewasa sebanyak 8 ekor.
b. Dalam usaha pemeliharaan kerbau rawa, rata-rata peternak memiliki luas kandang kerbau sebesar 0,005 ha untuk kandang pribadi, 0,005 ha untuk kandang kelompok dan 0,0003 ha untuk kandang komunal. Sedangkan untuk luas lahan penggembalaan, rata-rata peternak memiliki luas lahan sebesar 14,11 ha untuk lahan gembala pribadi dan 204,11 ha untuk lahan gembala komunal.
c. Usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok menghasilkan nilai NPV positif sebesar Rp. 772.911.745,- ; nilai IRR sebesar 30% dan Net B/C >1, yakni sebesar 791,42 yang artinya usaha pemeliharaan kerbau rawa pola kelompok layak untuk diusahakan. Sedangkan untuk usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individu juga menghasilkan nilai NPV positif sebesar Rp. 279.970.045,- ; nilai IRR sebesar 41% dan Net B/C>1, yakni sebesar 362,66 yang artinya usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individu layak untuk diusahakan.
d. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan kerbau rawa baik pola kelompok maupun individu tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan penerimaan. Dapat dikatakan usaha pemeliharaan kerbau rawa baik pola kelompok maupun individu layak secara finansial. . Jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa kedua jenis usaha lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
2. Jenis pupuk berpengaruh terhadap percepatan recovery dan peningkatan jumlah spesies rumput dan biomas pakan. Biomas yang diperoleh dari aplikasi pupuk organik, NPK dan Urea berturut-turut adalah sebanyak 18 kg, 6 kg dan 4 kg. a. Hasil perlakuan pupuk organik terhadap tanaman menghasilkan jumlah spesies yang
lebih banyak dibandingkan dengan perlukuan pupuk lainnya, yakni sebanyak 13 spesies.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 156
Sedangkan perlakuan pupuk Urea menghasilkan jumlah spesies yang paling sedikit, yakni sebanyak 3 spesies.
3. Jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi susu sehari-hari pada tiga Desa di Kecamatan Pampangan, yakni sebanyak 47 RT dengan persentase 78,3 persen dan rumah tangga yang tidak mengkonsumsi susu sebanyak 13 RT dengan persentase 21,7 persen. a. Jenis susu yang dikonsumsi paling banyak adalah jenis susu kemasan sehari-hari yakni
sebanyak 21 RT dengan persentase 31,0 persen dan jenis susu yang paling sedikit dikonsumsi adalah jenis susu kesehatan sebanyak 2 RT dengan persentase 3,0 persen.
b. Hasil analisis linier berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi RT dalam mengkonsumsi susu menghasilkan 1 variabel bebas yang berpengaruh terhadap volume konsumsi susu yakni, pendidikan. Sedangkan variabel pekerjaan utama KK, pendapatan RT, jumlah anggota keluarga, jenis rumah, luas rumah, luas pekarangan, luas lahan yang dimiliki dan jumlah kerbau yang dimiliki tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume konsumsi susu.
4. Uji sensoris (daya terima) yang dilakukan terhadap indikator aroma menghasilkan nilai tertinggi tingkat kesukaan panelis terhadap aroma minuman jeli susu kerbau rawa adalah perlakuan D (penambahan karagenan sebesar 0,65%, susu 40% dan air 60%). a. Uji sensoris (daya terima) yang dilakukan terhadap indikator tekstur menghasilkan nilai
tertinggi tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur minuman jeli susu kerbau rawa adalah perlakuan F (penambahan karagenan sebesar 0,65%, susu 60% dan air 40%).
b. Uji sensoris (daya terima) yang dilakukan terhadap indikator rasa menghasilkan tingkat kesukaan panelis terhadap rasa minuman jeli susu kerbau menurun dengan semakin rendahnya konsentrasi susu baik pada konsentrasi karagenan 0,55% maupun 0,65%.
c. Kandungan kimia pada minuman jeli susu kerbau rawa dengan formulasi penambahan karegenan 0,65% dengan rasio konsentrasi susu 60% dan air 40%, antara lain kadar air sebesar 77,60±0,26% ; kadar abu sebesar 0,79±0,00 ; protein sebesar 4,23±0,01% ; lemak sebesar 9,64±0,16% ; karbohidrat sebesar 7,71±0,34% ; dan kalori sebesar 135±1Kkal per 100 mL.
d. Usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa menghasilkan nilai NPV positif sebesar Rp. 22.860.389,58 ; nilai IRR sebesar 28% dan Net B/C> 1, yakni sebesar 1,95 yang artinya usaha pemeliharaan kerbau rawa pola individu layak untuk diusahakan.
e. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan penerimaan. Dapat dikatakan usaha pengolahan minuman jeli susu kerbau rawa layak secara finansial. Jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa usaha lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi biaya daripada sisi penerimaan.
5. Pilot project implementasi model paludikultur dan agroforestry pada lahan gambut di kecamatan pangkalan lampam desa perigi mampu mengembangkan 4 model paludikultur
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 157
yaitu Meranti-Nanas, Meranti-Cabe, Jelutung-Nanas dan Jelutung-Cabe dengan skala masing-masing 1 ha. a. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk model paludikultur dan agroforestry model
Meranti-Nanas dengan total sebesar Rp 29.137.574 selama 10 tahun, model Meranti-Cabe total sebesar Rp 33.111.000 selama 10 tahun. Model Jelutung-Nanas dengan total sebesar RP 53.123.576 selama 30 tahun, model Jelutung-Cabe dengan total sebesar Rp 48.011.950 selama 30 tahun.
b. Pendapatan yang diterima dari model paludikultur dan agroforestry model Meranti-Nanas dengan rata-rata sebesar Rp 56.849.292 selama 10 tahun, model Meranti-Cabe rata-rata sebesar Rp 43.893.635 selama 10 tahun. Model Jelutung-Nanas dengan rata-rata sebesar RP 143.944.421 selama 30 tahun, model Jelutung-Cabe dengan rata-rata sebesar Rp 135.124.245 selama 30 tahun.
c. Hasil analisis finansial semua model paludikultur dengan NPV bernilai positif, Meranti-Nanas dengan IRR 74,37% sedangkan Net BC 6,25, Meranti-Cabe dengan IRR 64,67% dan Net BC 5,63, Jelutung-Nanas dengan IRR 61% sedangkan Net BC 21,4 dan Jelutung-Cabe dengan IRR 48,4% dan Net BC 18,8. Dapat dikatakan semua model paludikultur dan agrofoestry layak secara ekonomi.
d. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan berbagai model paludikultur yang dikembangkan tidak sensitif baik terhadap peningkatan biaya maupun penurunan harga produk dan jumlah produksi. Dapat dikatakan memang pengembangan model paludikultur pada lahan gambut dalam kegiatan Pilot Project Implementasi Model Paludikultur dan Agroforestry layak secara finansial. Jika dibandingkan antara antara sisi penerimaan dan sisi biaya, tampak bahwa model paludikultur jelutung-cabe lebih sensitif terhadap perubahan dari sisi penerimaan daripada sisi biaya.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 158
DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, W. C,. I N.N, Suryadiputra, Bambnag Hero Saharjo dan Labueni
Agus, F, dan IG.M. Subiksa.2008. Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Andriesse, J.P. 1988. Nature and Management of Tropical Peat Soils. Journal Food & Agricilture Organization of The United Nations. Rome.
Ariningsih, Ening. 2008. Pengaruh – Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Konsumsi Susu dan Produk Olahan Susu. http://peternakan.litbang.pertanian. go.id/fullteks/lokakarya/loksp08-66.pdf. Diakses pada Jum’at, 29 Juni 2018
pukul 23.35 WIB.
Asterina, F dan Sutina. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Ogan Komering Ilir. Jurnal Abdimas Mandiri Volume 1 No. 2. Palembang
Barkah, B. & Siddiq, M. (2009). Penyekatan parit/kanal dan pengelolaan bersama masyarakat di areal hutan rawa gambut MRPP Kabupaten Musi Banyuasin. Report No. 20/TA Final/SOP. No.03. PSF Rehabilitation Rev.0. Palembang, Indonesia: German Technical Cooperation – Merang REDD Pilot Project (MRPP).
Bastoni dan Tim Peneliti Balai Litbang LHK Palembang, 2017.Tanaman dan Teknik Revegetasi untuk Restorasi Ekosistem Gambut.Bahan Paparan Round Table Discussion (RTD) Konsorsium PETUAH-CoE PLACE, Swarna Dwipa, 2 Februari 2017.
Bastoni. 2014. Budidaya jelutung rawa (Dyera lowii). Palembang: Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BBSDLP. 2014. Sumber Daya Lahan Pertanian Indonesia, luas, penyebaran dan potansi ketersediaan. Laporan Teknis Nomor 1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.
Biancalani, R., & Avagyan, A. (2014). Towards Climate-Responsible Peatlands Management. Rome: FAO.
BPS. 2017. Populasi Kerbau Menurut Provinsi, 2009 – 2017. https://www. bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1020. Diakses pada Minggu, 29 Juli 2018 pukul 14.02 WIB.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 159
BPS. 2017. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
BPS. 2017. Produksi Susu Segar Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2017. https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1083. Diakses pada Minggu, 5 Agustus 2018 pukul 16.25 WIB
BPS Sumatera Selatan. 2016. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Di Provinsi Sumatera Selatan. https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/ 2016/11/03/219/populasi-ternak-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-ternak-di-provinsi-sumatera-selatan-2015.html. Diakses pada Rabu, 18 Juli 2018 pukul 23.52 WIB.
BPS Sumatera Selatan. 2017. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 2017. Palembang: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan.
BPTP Sumatera Selatan. 2011. Kerbau Pampangan. http://sumsel.litbang.pertanian. go.id/index.php/plasma-nutfah/kerbau-pampangan. Diakses pada Rabu, 18 Juli 2018 pukul 03.31 WIB.
Daisuke, H., Tanaka, K., Jawa, K.J., Ikuo, N., & Katsutoshi, S. 2013. Rehabilitation of degraded tropical rainforest using Dipterocarp trees in Serawak, Malaysia. International Journal of Forestry Research. http://dx.doi.org/10.1155/2013/ 683017.
Departemen Kesehatan. 2014. Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Destriana, Abdik. 2008. Perilaku Konsumsi Susu Pada Konsumen Keluarga di Wilayah Babakan Kecamatan Dramaga Bogor (Skripsi). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Dinas Peternakan. 2006. Statistik Peternakan 2006. Direktorat Jenderal Peternakan Deptan. RI. Jakarta
Dinas Peternakan OKI. 2011. Perkembangan Program Aksi Pembibitan Kerbau Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. https://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/plkbo11-27.pdf?secure=1. Diakses pada Rabu, 18 Juli 2018 pukul 23.09 WIB.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2016. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017. http://ditjenpkh.pertanian.go.id. Diakses pada Sabtu, 20 Oktober 2018 pukul 11.48 WIB.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 160
Giesen, W. (2015). Utilising non-timber forest products to conserve Indonesia’s peat
swamp forests and reduce carbon emissions. Journal of Indonesian Natural History. 3(2):10-19.
Hadiati, S. Dan Indriyani, N, L, P. 2008. Petunjuk Teknis Budidaya Nenas. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika.
Hadisuparto, H., 2004. Peat Swamp Forest as a Natural Resources and Enviromental Guardianship. Makalah Lokakarya Penangan Kawasan Eks PLG. Kalimantan Tengah.
Haryono. 2013. Strategi dan Kebijakan Kementerian Pertanian dalam Optimalisasi Lahan Sub-optimal Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
Huppertz, L., Kelly, A.L. 2009. Properties and Constituents of Cow’s Milk dalam
Tamime, AY (Ed.) Milk Processing and Quality Management. Oxford: Blackwell Publishing.
IDFA. Tanpa Tahun. Definitions. https://www.idfa.org/news-views/media-kits/ milk/definition. Diakses pada Senin, 30 Juli 2018 pukul 01.12 WIB.
Irawan. 2007. Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Pendekatan Nilai Manfaat Multifungsi Lahan Sawah dan Lahan Kering (Studi Kasus di Sub DAS Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Jaenicke, J., Wosten, H., Budiman, A., Siegert, F. 2010. Planning hydrological restoration of peatlands in Indonesia to mitigate carbon dioxide emissions. Mitig Adapt Strateg Glob Chang, 15: 223–239
Joosten, H., Dommain, R., Haberl, A., Peters, J., Silvius, M., & Wichtmann, W.
(2012). Implementation. In: Joosten, H., Tapio-Bistrom, M.L., & Tol, S. (eds). Peatlands – guidance for climate change mitigation through conservation and sustainable use. 2nd ed. pp:9-21. Rome: FAO and Wetlands International.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut. http://pkl.menlhk.go.id
Las, I., M. Sarwani, A. Mulyani, dan M.F. Saragih. 2012. Dilema dan rasionalisasi kebijakan pemanfaatan lahan gambut untuk areal pertanian. Dalam Husen et al. (Eds.). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Badan Litbang Pertanian. Kementrian Pertanian. Halaman:17-29.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 161
Mangkunegara dalam Erni. 2013. Pengaruh Pembelajaran Ekonomi dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi (Skripsi). Universitas Tanjungpura. Pontianak.
Maryana, Y.E. 2018. Teknologi Pengolahan Es Krim Dari Susu Kerbau Rawa. http://sumsel.litbang.pertanian.go.id/BPTPSUMSEL/halkomentar-teknologi-pengolahan-es-krim-dari-susu-kerbau-rawa-2.html#ixzz5LXi6XD2s. Diakses pada Rabu, 18 Juli 2018 pukul 02.47 WIB.
Masganti, T. Notohadikusumo, A. Maas, dan B. Radjagukguk. 2002. Efektivitas dan pemupukan P pada tanah gambut. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan 3(2):38-48.
Matondang, Rasali Hakim dan Talib, Chalid. 2015. Pemanfaatan Ternak Kerbau Untuk Meningkatkan Produksi Susu. Jurnal Litbang Pertanian Vol. 34 (1): 41-49.
Murti, T.W. 2002. Ilmu Ternak Kerbau. Kanisius: Yogyakarta. P. 34-167.
Myers, P. et al. 2018. Bubalus Bubalis. http://animaldiversity.org/accounts/ Bubalus_bubalis/classification/. Diakses pada Kamis, 19 Juli 2018 pukul 00.43 WIB.
Nduru, B. 2018. Paludikultur Solusi Pemberdayaan Lahan Gambut Lestari. http://elang.or.id/2018/01/paludikultur-solusi-pemberdayaan-lahan-gambut-lestari/.
Noor, M. 2001. Pertanian Lahan Gambut. “Potensi dan Kendala”. Kanisius.Yogyakarta
Noor, E.F. 2011. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Di Provinsi Kalimantan Timur. JPSL Vol.(1)1: 38–46, Juli 2011. Bogor.
______. 2004. Lahan Rawa. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Nurbaiti, N. 2015. Analisis Profitabilitas Usaha dan Nilai Tambah Produk Olahan Ikan
Bandeng Pada Usaha Aneka Olahan Ikan Bandeng Mama’s (skripsi). Institut
Pertanian Bogor. Bogor. Nurhayati et. al. 2014. Pengelolaan Kesuburan Tanah, Produktivitas, Dan Keuntungan
Sistem Tumpangsari (Kelapa Sawit + Nenas) Di Lahan Gambut Provinsi Riau.
Osamaleli. 2014. Analisis Ekonomi Dan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 162
Pandey dan Voskuil dalam Damayanthi et al. 2014. Karakteristik Susu Kerbau Sungai dan Rawa di Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) Vol. 19 (2): 67-73.
Prastiwi, W.D. dan Setiawan, H. 2016. Persepsi Konsumsi Susu Cair Masyarakat Di Daerah Perkotaan Dan Perdesaan. Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Agromedia Vol. 34 (1).
Pantau Gambut. 2018. Langkah-langkah Restorasi Gambut. http://pantaugambut.id/ pelajari/pemulihan/lahan-gambut/langkahlangkah-restorasi-gambut
Pradhanand. 2015. Analisis Profitabilitas Usaha dan Nilai Tambah Produk Pada Usaha
Mikro Keripik Singkong Geprek di Kabupaten Bogor (skripsi) Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Prasetyo, Sigit. 2012. Teori Konsumsi. http://staff.unila.ac.id/sigit/?s=teori+konsumsi. Diakses pada Kamis, 12 Juli 2018 pukul 23.26 WIB.
Prayitno Bambang dan Munandar. 2016. Pengetahuan Hijau Berbasis Kebutuhan dan Kearifan Lokal untuk Mndukung Pembangunan Berkelanjutan. “Pengelolaan
Lahan Gambut Untuk Agroforesty dan Paludikultur”. Konsorsium “PETUAH”
perguruan tinggi untuk indonesia hijau, MCA-Indonesia.
Puslitbangtan. 2007. Peluang dan Tantangan “Revolusi Putih”. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 29 (5): 12-13.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Sekertariat Negara. Jakarta.
Resnawati, Heti. 2012. Kualitas Susu Dalam Berbagai Pengolahan Dan Penyimpanan. Semiloka Nasional Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas – 2020. Balai Penelitian Ternak. Bogor.
Retnaningsih. 2008. Perilaku Konsumsi Susu Pada Wanita Dewasa di Jakarta Timur. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Roth, R.A. 2011. Nutrition & Diet Theraphy, 10th Edition. Delmar: Cengage Learning.
Savitri, T. 2018. Kebutuhan Gizi Setiap Orang Berbeda – Beda, Bagaimana Cara Menghitungnya?. https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/cara-menghitung- kebutuhan-gizi/. Diakses pada Senin, 30 Juli 2018 pukul 00.01 WIB.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 163
Setiadi, N. J. 2003. Perilaku Konsumen. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=HdxDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=definisi+konsumen+menurut&ots=PlLhAgXOGU&sig=tYZ-v-_UDjDguUX2uKoZTjpQTUI&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20konsumen%20menurut&f=false. Diakses pada Senin, 30 Juli 2018 pukul 03.46 WIB.
Setiawan, A.B. 2016. Konsumsi Susu Pada Anak Sekolah Dasar Kota Bandar Lampung.http://digilib.unila.ac.id/21851/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Skripsi: Universitas Lampung. Diakses pada Kamis, 12 Juli 2017 Pukul 09.49 WIB.
Shiodera, S., Atikah, T.D., Apandi, I., Seino, T., Haraguchi, A., Rahajoe, J.S., and Kohyama, T.S. 2016. Peat-Fire Impact on Forest Structure in Peatland of Central Kalimantan. In Osaki M and Tsuji N (Eds). Tropical Peatland Ecosystems. Springer Japan
Siboro. 2005. Panduan Kebakaran dan Lahan Gambut. Proyek Climate Chane, Forest and
Peatlands in Indonesia. Wetlands International - Indonesia Progamme dan Wildlife Habitat Cnada. Bogor. Indonesia
Soeherman, Y. 2015. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Rumah Tanga Dan Pola Konsumsi Susu Pada Anak Di Desa Candibangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta (Skripsi). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Stanturf J., Lamb, D., & Madsen, P. 2012. Forest Landscape Restoration: Integrating Natural and Social Sciences. Springer.
Suriadikarta. D.A. 2012. Teknologi Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Jurnal Sumberdaya Lahan Pertanian 6 (2), 197 – 211. Badan Penelitian Tanah dan Pengembangan Pertanian.
Tariq M., Younas M., Khan A.B., dan Schlect E. 2013. Body Measurements and Body Condition Scoring as Basis for Estimation of Live Weight in Nili-Ravi Buffaloes. Pakistan Veterinary Journal Vol. 33 (3): 325-329.
UN Food and Agriculture Organization. 2013. Milk and Dairy Products in Human Nutrition. Roma: UN FAO.
UN Food and Agriculture Organization dan World Health Organization. 2011. Codex Alimentarius: Milk and Milk Products – Second Edition. Roma: UN FAO dan WHO.
Laporan Akhir 2018
Kajian Profitabilitas dan Keekonomian Komoditi Ramah Gambut Kab. OKI 164
Wahyuni et. al. 2014. Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove Di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur . Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No.1, April 2014 : 1 – 12. Samarinda
Wahyunto, dan Ai Dariah. 2013. Pengelolaan lahan gambut terdegradasi dan terlantar untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam Haryono et al. (Eds.). Politik Pengembangan Pertanian Menghadapi Perubahan Iklim. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Halaman:329-348.
Wildayana E dan M. Edi Armanto. 2009. Dampak finansial kehilangan hara ke atmosfer akibat kebakaran hutan dan lahan. Jurnal Habitat Volume XX (2) : 81-88 Agustus 2009.
Zulfikar. 2006. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut dengan Pola KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam: Rimbawanto et al. (ed). Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa Secara Bijaksana dan Terpadu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, Badan Litbang Kehutanan. p 7-13.