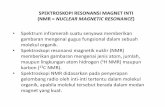KUMPULAN ARTIKEL DARI RESONANSI REPUBLIKA
-
Upload
alsyukrouniversal -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of KUMPULAN ARTIKEL DARI RESONANSI REPUBLIKA
1. Patriotisme ………………………………………………………………..…………………………………………………… 3
2. Terusiknya kedaulatan kita ………………………………………………………………... 6 3. Mentri susi yang fenomenal…………….…………………………………………………… 9
4. Suatu hari di kampong tartar …………….……………………………………………….. 14 5. Budaya Politik Indonesia……………………………………………………………………….. 17
6. ISIS Menyasar Mahasiswa Al Azhar Kairo…………………………………………….. 20 7. Pahlawan dan Kita ………………………………………………………………………………….. 25
8. Mobil Amien Rais Ditembak……………………………………………………………………….28 9. Masjid Cordova……………………………………………………………………………………………32
10. Tukang Cat ………………………………………………………………………………………………35 11. Bravo Swedia! …………………………………………………………………………………………38
12. Sumpah Pemuda dan Bola Indonesia……………………………………………………..41 13. Kabinet Kerja Keras…………………………………………………………………………………44
14. Kajian Islam CUHK (1)…………………………………………………………………………….48
15. Kajian Islam CUHK (2)…………………………………………………………………………….52 16. Presiden Baru, Harapan Baru………………………………………………………………….55
17. Solusi BBM dengan Mobil Listrik……………………………………………………………..59 18. 'Revolusi Payung' dan Muslimin Hong Kong……………………………………………62
19. Restorasi GBHN………………………………………………………………………………………..65 20. Danau Dendam tak Sudah……………………………………………………………………….69
21. Nobel Perdamaian Buat Sweet Seventeen………………………………………………71 22. Ebola, Virus yang tak Memandang Kewarganegaraan……………………………76
23. Winners Take All ……………………………………………………………………………………..79 24. Basis Karakter Kemajuan…………………………………………………………………………82
25. Basis Karakter Kemajuan (2}…………………………….……………………………………93 26. Basis Karakter Kemajuan (3)……………………………………………………………….…97
27. Basis Karakter Kemajuan (4)……………………………………………………………….100 28. Islam dalam krisis (1) …………………………………………………………………….103
28. Reference sites ………………………………………………………………………………….. 106
Patriotisme Tuesday, 18 November 2014, 06:00 WIB Sumber : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/17/nf6t6m-patriotisme
Professor Ahmad Syafii Maarif
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh:Ahmad Syafii Maarif
Menurut Wikipedia, patriotisme sebagai kata benda abstrak baru muncul di
Eropa awal abad ke-18. Hulu konsep patriotisme bisa dilacak kepada bahasa
Latin abad ke-6 patriota atau bahasa Yunani kuno patriotes yang bermakna
warga senegeri atau sebangsa. Maka patriotisme tidak lain keterikatan
kultural kepada sebuah tanah air atau pengabdian kepada sebuah negeri
dengan penuh cinta.
Jika nasionalisme merupakan sebuah konsep atau ideologi politik radikal
yang bertujuan untuk mengubah keadaan suatu bangsa kepada sesuatu
yang dibayangkan lebih baik, maka patriotisme lebih bersifat konsep
kultural, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Seorang
nasionalis pastilah seorang patriot, tetapi seorang patriot belum tentu
seorang nasionalis.
Di kalangan kaum nasionalis Muslim Indonesia, telah lama dikenal
diktumhubbu 'l-watan min al-iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman),
sebagaimana pernah saya dengar dari almarhum Roeslan Abdoelgani. Ini
bukti bahwa umat Islam Indonesia adalah patriot dan sekaligus nasionalis.
Saya tidak tahu dari mana sumbernya ungkapan ini, tetapi tentunya bukan
dari literatur hadis. Adalah sebuah fakta keras sejarah, patriotisme dan
nasionalisme umat Islam nusantara untuk melawan pihak asing, jauh
sebelum nama Indonesia muncul, sudah dirasakan sangat tinggi, sekalipun
cakupannya lebih terbatas kepada satu suku bangsa atau kerajaan tertentu.
Barulah pada 1920-an berkat kerja keras Perhimpunan Indonesia (PI) di
negeri Belanda, kemudian disusul oleh Sumpah Pemuda 1928 di Tanah Air,
gagasan keindonesiaan semakin mengental dan mengarah kepada cita-cita
kemerdekaan.
Dalam tradisi politik umat Islam sebagaimana terbaca dalam karya Ibn
Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyyah (halaman 139) juga ada diktum yang
tidak kurang seramnya: Inna 'l-Sultan dillu Allah fi 'l-ard, sittuna sanat min
imam jair aslah min lailatin. (Sesungguhnya sultan/penguasa adalah
bayangan Tuhan di muka bumi, 60 tahun di bawah pemerintahan sultan
yang jahat lebih baik daripada semalam tanpa sultan).
Bagi saya ungkapan-ungkapan yang membela penguasa yang jahat dan
culas tidaklah layak bagi dunia beradab. Apalagi dari sisi pandangan
Alquran, seorang patriot-nasionalis tidak hanya bertugas memerintahkan
yang baik-baik (al-ma'ruf), tetapi juga sekaligus mencegah kemungkaran
(al-munkar) dengan segala daya dan upaya. Sebab, tanpa itu semua,
sebuah masyarakat yang hendak ditegakkan atas landasan nilai-nilai moral
dan etika menjadi tidak mungkin. Indonesia yang berpenduduk mayoritas
Muslim itu sudah lama tersesat dalam kubangan amoral yang sarat dengan
kemungkaran ini.
Maka ke depan, tugas dan kewajiban utama para patriot-nasionalis adalah
membebaskan bangsa dan negara ini dari kelakuan anak-anaknya yang
curang dan mati rasa, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan
oleh semua.
Pertanyaan saya: berapa persen di antara elite dan penjabat negara kita
yang masih yang mendasarkan laku dan tindakannya kepada patriotisme?
Boleh jadi jumlahnya semakin meredup. Bagi saya, masalah patriotisme ini
menjadi sangat serius untuk ditancapkan kembali ke dalam jiwa bangsa ini.
Terusiknya Kedaulatan Kita
Minggu, 16 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/14/nf17sj-terusiknya-kedaulatan-kita
Asma Nadia
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Hari Pahlawan baru saja berlalu, tetapi berita yang mengiringi peringatan
para pahlawan pendahulu yang memperjuangkan kedaulatan justru berisi
kenyataan yang mengusik rasa nasionalisme kedaulatan kita.
Satu kabar memilukan datang dari Desa Kinokot, Nunukan, Kalimantan
Utara, di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Seluruh warga desa
memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Mereka
memilih Malaysia karena merasa lebih diperhatikan Pemerintah Malaysia.
Dari negeri jiran tersebut mereka mendapat gaji, fasilitas pendidikan, dan
kebutuhan lain.
"Warga desa ini seluruhnya 100 persen memilih menjadi warga negara
Malaysia," kata Ramli, anggota DPRD yang mendapat laporan setelah
mengunjungi kawasan perbatasan bersama kolega dari DPRD Nunukan.
Risiko jangka panjang yang mengkhawatirkan adalah desa yang masuk
wilayah Indonesia itu bisa diklaim sebagai bagian Malaysia karena berada di
zona perbatasan dan penduduknya memilih menjadi warga negara Malaysia.
Bukankah Sipadan dan Ligitan hilang dari kedaulatan Indonesia dengan
pertimbangan Malaysia dimenangkan karena sudah membangun
infrastruktur lebih dahulu di sana? Lalu, apa tindakan kita? Selamatkan
saudara-saudara di perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan
perhatian, bukan dengan kekerasan.
Berita lain yang juga mengusik kedaulatan adalah tercatatnya warga negara
Indonesia (WNI) dalam wajib militer Singapura. Ketika TNI dan Singapura
mengadakan latihan bersama di Magelang, dua prajurit yang didaftarkan
untuk ikut latihan adalah WNI. Mereka ternyata permanent resident di
Singapura dan wajib harus ikut dalam wajib militer.
Sedangkan dari sisi hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang
Kewarganegaraan 2006, WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya jika
yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa mendapat izin
terlebih dahulu dari Presiden. Akibatnya, kedua WNI tersebut dideportasi
kembali ke Singapura dan tidak ikut berpartisipasi dalam latihan bilateral.
Berita ketiga terkait pelanggaran kedaulatan negara yang cukup membuat
kita miris. Sebuah pesawat asing melanggar wilayah udara Indonesia,
melintas tanpa izin. Setelah dipaksa mendarat, pesawat tersebut didenda Rp
60 juta dan terbang kembali.
Apa yang memprihatinkan? Untuk mengejar pesawat tersebut, TNI AU harus
menerbangkan dua jet Sukhoi yang sekali terbang, masing-masing pesawat
memakan biaya operasional Rp 400 juta. Artinya, untuk force
down (memaksa turun) saja biayanya mencapai Rp 800 juta, tapi pelanggar
hukum hanya didenda Rp 60 juta. Padahal, hukum yang berlaku
memungkinkan pesawat tersebut didenda sampai Rp 2 miliar.
Pesawat yang tidak memiliki flight approval, yang merupakan salah satu
syarat terbang antarnegara, adalah milik pemerintahan Arab Saudi yang
melintasi Indonesia menuju Australia guna mempersiapkan kunjungan raja
Saudi ke Benua Kanguru tersebut.
Perizinan seperti ini seharusnya tidak memakan waktu lama karena
persahabatan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin baik, tapi mengapa
mereka tidak mengurus perizinan sejak awal? Mengapa juga denda yang
dikenakan begitu kecil, mengingat negara pelanggar juga mempunyai
sumber dana untuk membayarnya? Mengapa pula bangsa Indonesia yang
harus menanggung biaya yang diakibatkan pelanggaran bangsa asing?
Semua berita di atas seharusnya menyentak seluruh rakyat untuk kembali
kepada spirit perjuangan pada masa lalu demi mempertahankan kedaulatan.
Hanya saja jika dulu mempertahankan kedaulatan dengan kekuatan militer,
kini selain kekuatan militer, kita harus memperjuangkan kedaulatan dengan
kekuatan ekonomi, kekuatan kesejahteraan, kekuatan persatuan, diplomasi,
dan kekuatan apa pun yang kita miliki.
Jika Indonesia kuat dan sejahtera, tidak hanya bangsa sendiri yang bangga
dan menghargai, bangsa lain pun akan ikut menghormati.
Menteri Susi yang Fenomenal
Friday, 14 November 2014, 06:00 WIB
Nasihin Masha
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha
Matanya selalu berbinar dan tajam. Pertanda cerdas dan percaya diri.
Suaranya ngebas, pertanda perokok berat. Rambutnya selalu diikat di
belakang, di bagian depan dibiarkan tak rapi. Pertanda energik. Langkahnya
pun cepat. Pertanda gesit dan cekatan.
Itulah Susi Pudjiastuti, menteri kelautan dan perikanan. Susi adalah menteri
yang paling fenomenal, dilihat dari kontroversi personalnya maupun
gebrakan awalnya.
Selama ini publik lebih mengenal Susi sebagai pemilik maskapai
penerbangan Susi Air. Ia juga dikenal sebagai pemilik usaha perikanan,
terutama lobster. Nama Susi juga banyak disebut ketika ada musibah
tsunami Aceh. Namanya sangat harum. Bagi publik yang pernah
berhubungan dekat dengan Susi pasti akan banyak mengenal pribadi Susi.
Susi adalah fenomena khas anak reformasi, seperti halnya Jokowi, sang
presiden.
Walau bisnisnya sudah dilakukan selama 25 tahun, tapi reformasi telah
melahirkan apa pun, termasuk melejitkan usaha dari sudut Pantai
Pangandaran, Jawa Barat. Susi tak pernah menutupi simpatinya kepada
PDIP dan kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri.
Susi berijazah SMP. Pendidikannya terhenti saat kelas dua SMA di
Yogyakarta. Ada musibah. Kepalanya terbentur saat terjatuh. Namun,
langkahnya untuk berhenti sama sekali dari sekolah tak urung membuat
ayahnya sewot. Susi mengaku tak diajak bicara oleh ayahnya selama satu
tahun. Jenjang pendidikan inilah yang sempat mencuatkan tanggapan
miring.
Namun, banyak orang sukses yang tak lulus perguruan tinggi. Apalagi,
teman SMA-nya yang bergelar profesor di perguruan tinggi ternama
bertestimoni bahwa Susi sudah mahir berbahasa Inggris sejak SMA, bahkan
biasa melahap buku-buku berat sejak SMA. Saat presentasi di depan para
pemimpin redaksi, Susi tak bisa menutupi bahwa ia lebih fasih
mengekspresikan ide-idenya dalam bahasa Inggris. Bukan “Inggris-Jawa”
atau “Inggris-Indonesia”, susunan kalimatnya benar-benar seperti orang
yang sejak lahir berbahasa ibu bahasa Inggris. Banyak orang yang pernah
tinggal lama di luar negeri tapi bahasa Inggrisnya tetap saja Inggris-
Indonesia-sesuatu yang wajar sebetulnya.
Orang tuanya bukan termasuk miskin. Ayahnya, H Ahmad Karlan, pensiunan
PNS. Ibunya, Hj Suwuh Lasminah, adalah anak H Ireng yang dikenal
memiliki banyak tanah. Tak heran jika Susi bisa memilih sekolah terbaik di
Yogyakarta, SMAN 1, dan bukan di Pangandaran.
Susi adalah anak pertama dari empat bersaudara, ia juga memiliki saudara
tiri. Sebelum menikah dengan ibunya, H Karlan adalah duda. Namun, saat
merintis usahanya, Susi tak menggantungkan pada kekayaan orang tuanya.
Ia membanting tulang. Performa tubuhnya dan rahangnya menunjang Susi
menjadi “wanita macho”.
Ia mengendarai sendiri truk ikannya di jalanan pantura, saat ia boyongan
bersama anaknya ke Cirebon-setelah pernikahannya yang pertama kandas.
Pernikahannya yang kedua pun-dengan pria bule-kandas. Ia tipikal wanita
mandiri dan petarung. Garis di wajahnya menunjukkan dirinya sebagai
orang yang keras pada pendirian.
Cara jalan, gerak tubuh, dan gaya bicaranya menunjukkan bahwa ia orang
yang cuek. Tak mengherankan jika kemudian ia mengukir betis kanannya
dengan tato. Sebuah lukisan bergambar burung phoenix. Tato itu dibuat di
Bali. Merokok dan bertato adalah kontroversi yang mengusik perasaan
publik.
Bagi sebagian orang, merokok itu bukan simbol yang baik. Iklan rokok pun
diembeli ancaman penyakit dan gambar organ tubuh yang rusak akibat
merokok. Karena itu, ketika ia tertangkap merokok di Istana, itu menjadi
berita besar. Ia lupa bahwa dirinya sudah menjadi pejabat.
Bagi para pendukungnya, ia dibela dengan menjajarkan Susi dengan figur
korup seperti Ratu Atut yang bahkan berjilbab. Sesuatu yang tak bijak dan
sama sekali keluar dari konteks. Publik berhak menuntut kesempurnaan dari
para pejabatnya. Salah satu faktor paling penting dalam membangun
masyarakat adalah hadirnya keteladanan. Keteladanan selalu dekat dengan
tuntutan kesempurnaan. Kita bersyukur bahwa kemudian Susi menyatakan
akan menghilangkan kebiasaan merokoknya di depan umum. Ia juga lebih
sering bercelana panjang untuk menutupi tatonya.
Namun, Jokowi tentu memiliki alasan mengapa memilih Susi. Jokowi atau
mungkin Megawati sadar atas pilihannya ini. Nama Kabinet Kerja sangat
sahih dinisbatkan ke Susi. Ia model ideal untuk kerja keras. Susi pun
membuktikannya. Ia menghibahkan gajinya sebagai menteri untuk premi
asuransi nelayan.
Menurutnya, problem perikanan adalah illegal fishing, unreported fishing,
dan unregulated fishing. Ia juga mencatat Indonesia adalah satu-satunya
negara di dunia yang mengizinkan lautnya dipanen nelayan asing. Di sini
pun ada ironi. Nelayan kecil dikenakan banyak pungutan, untuk nelayan
asing malah sebaliknya. Mereka hanya dikenakan pungutan Rp 8.000
pergross ton. “Lebih murah dari rokok saya,” kata Susi.
Ada ribuan kapal asing yang berkeliaran di laut Indonesia. Mereka dari
Thailand, Taiwan, Vietnam, Cina. Tak heran jika pendapatan dari sini hanya
Rp 250 miliar per tahun. Ia menargetkan untuk naik 508 persen, menjadi Rp
1,277 triliun. Ia juga melakukan moratorium kapal asing. Kita berharap Susi
akan menggebah nelayan asing dari laut Indonesia.
Ada terlalu banyak ironi dalam pengelolaan laut kita: regulasi yang
menguntungkan nelayan asing dan menghisap nelayan lokal, jumlah kapal
patroli milik TNI dan Polri terlalu sedikit dan yang bisa operasi pun cuma 30
persen (itu pun digunakan secara bergilir), penegakan hukum yang lemah,
subsidi BBM nelayan sebagian sangat besar diambil nelayan asing, jumlah
kapal asing lebih banyak dari yang diizinkan. “Kita kasih mati orang kita
sendiri,” katanya geram.
Susi yakin jika dikelola dengan baik, pendapatan negara dari laut bisa
menggantikan pendapatan dari migas. Ia akan bekerja dengan cara yang ia
biasa lakukan. Menurutnya, kini bukan saatnya lagi rezim anggaran tapi
rezim kerja. Susi mengaku tak menerima amanat sebagai menteri jika
bukan karena faktor Jokowi.
Kitab Assiyasatus-Syar'iyyah fi Ishlahir-Ra'iy war-Ra'iyah adalah kitab paling
penting dalam khazanah Islam tentang politik. Kitab karya Ibnu Taimiyah ini
diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Bulan Bintang dengan
judul Pedoman Islam Bernegara. Ia membuka bukunya dengan judul
kepemimpinan. Pada bagian ini ia menekankan tentang pentingnya
kecakapan dalam mengangkat seseorang. Jika pengangkatan itu atas dasar
kedekatan maupun harta, sesungguhnya itu adalah pengkhianatan. Jabatan
juga jangan diberikan kepada orang yang menuntut jabatan itu.
Memilih yang cakap pun tak mudah. Karena itu, Ibnu Taimiyah mengusulkan
untuk memilih yang terbaik dari yang ada. Pilihlah yang lebih utama sesuai
jabatannya, dengan dua rukun: kuat dan bisa dipercaya. Kata kuat bisa
disesuaikan dengan jenis bidangnya. Jika masih sulit mendapatkannya,
carilah yang paling bisa memberikan manfaat di bidang yang akan
dipimpinnya.
Pada akhirnya, semuanya menjadi sempurna jika kita mengetahui motif dan
metode yang akan dilakukan seorang pemimpin. Di sinilah pentingnya visi
kita dalam berbangsa dan bernegara. Jokowi sudah mencanangkan Trisakti
dan Nawacita. Mari kita nilai para menteri ini atas dasar ideologi (motif dan
metode) ini.
Susi, buktikan bahwa Anda adalah pilihan terbaik bagi negeri ini, yang
memberi manfaat bagi khalayak. Amanah ini adalah jalan menuju
kesempurnaan dan keteladanan.
Suatu Hari di Kampung Tatar
Thursday, 13 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/12/nexo2r-suatu-hari-di-kampung-
tatar
Azyumardi Azra
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
Orang-orang Tatar agaknya merupakan salah satu bangsa yang paling
terpencar di muka bumi ini sejak waktu lama. Kini bermukim di berbagai
negara, tidak ada angka pasti berapa jumlah mereka, walau berbagai
estimasi memperkirakan jumlah mereka sekitar 10 juta jiwa pada 2000.
Suku Tatar belakangan ini menjadi bagian dari berita krisis di Ukraina ketika
bagian tenggara negara ini sejak akhir Februari 2014 berusaha melepaskan
diri dengan bantuan Rusia. Suku Tatar yang bermukim di Semenanjung
Krimea ibarat terjepit di antara dua kekuatan: pemerintah pusat Ukraina di
Kiev yang memerangi kaum separatis di Donetsk.
Secara tradisional, mereka menjadi sasaran kecurigaan Moskow. Bahkan,
pada 1944 atas perintah Joseph Stalin, secara massal mereka diusir dari
Semenanjung Krimea walaupun kemudian mereka direpatriasi.
Berasal dari nenek moyang bangsa Turki, orang-orang Tatar kini paling
banyak bisa ditemukan di Republik Tatarstan yang merupakan bagian
Federasi Rusia. Pernah berkunjung pada Juni 2009 ke Kazan, ibu kota
Republik Tatarstan, penulis Resonansi ini menyaksikan lanskap yang
berbeda dengan wilayah Federasi Rusia lain: di mana-mana terlihat banyak
masjid dan madrasah, bahkan juga universitas Islam. Warga Tatar adalah
kaum Muslim wasathiyyah.
Penulis Resonansi ini juga menemukan kampung Tatar Muslim di Polandia.
Bersama delegasi Dialog Antaragama Indonesia-Polandia III awal November
2014, Ahad (2/11), penulis mengunjungi dua masjid Tatar di kawasan
Provinsi Bialystok, sebelah timur laut Warsawa, ibu kota Polandia. Komunitas
Muslim Tatar ini adalah komunitas Muslim yang sudah berusia panjang —
melewati berbagai perang dan pergolakan politik, tapi tetap bertahan. Kini
mereka menjadi bagian terbesar dari sekitar 5.000 Muslim Polandia.
Orang-orang Tatar mulai datang dari kawasan Volga dan menetap di wilayah
Polandia sejak 1379. Banyak di antara mereka semula adalah prajurit Tatar
yang ikut berperang melawan Kerajaan Tetonik dalam pertempuran
Grunwald 1410 di Malbork, wilayah utara Polandia sekarang. Perlahan tapi
pasti mereka membentuk komunitas distingtif setidaknya di dua desa di
Provinsi Podlaskie, sekitar 180 kilometer arah timur laut Warsawa.
Komunitas Muslim Tatar sering berjuang membela Kerajaan Polandia
sehingga mereka dianugerahi tanah oleh Raja Polandia untuk membangun
desa. Dalam Perang Dunia II banyak warga Tatar Polandia diusir Jerman ke
Siberia, seusai perang mereka berimigrasi ke Inggris, Amerika Serikat, dan
Australia.
Secara jumlah, Muslim Tatar Polandia tidak signifikan karena jika bicara
tentang „agama‟ di Polandia, yang dimaksud adalah Katolik yang berjumlah
sekitar 90 persen dari 39 juta penduduk. Apalagi Paus Johanes Paul II
(1920-2005) berasal dari Polandia. Namun, kaum Muslim Tatar cukup solid.
Sejak 1936 mereka mendirikan Persatuan Muslim Polandia.
Salah satu distingsi kaum Muslim Tatar Polandia adalah masjid yang bukan
hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat komunitas. Ada tiga masjid
Tatar di Polandia: Kruszyniany, Bohoniki, dan Gdansk —yang pernah
menjadi pusat organisasi buruh Solidaritas pimpinan Lech Walensa.
Masjid pertama didirikan pada 1768-1795 di Desa Kruszyniany, sekitar 50
kilometer dari Bialystok, ibu kota Provinsi Podlaskie. Berkunjung ke masjid
tua ini terlihat masih kokoh. Dapat menampung sekitar 100 jamaah, bagian
dalam masjid kecil ini juga memiliki „mezanine‟ yang biasanya digunakan
untuk Muslimah. Masjid yang ini meski memiliki dua menara yang sedikit
lebih tinggi, tidak tinggi dari bangunan utama, mirip gereja dan rumah
tradisional. Meski kecil, bangunan ini memang betul-betul masjid, lengkap
dengan mihrab dan mimbar.
Masjid Tatar kedua terletak di Desa Bohoniki, dekat Kota Sokolta, sebelah
timur laut Bialystok. Menurut penuturan komunitas Tatar yang tinggal di
sekelilingnya, masjid ini didirikan pada pertengahan akhir abad ke-17 atau
awal abad ke-18. Masjid Bohoniki yang sedikit lebih kecil daripada Masjid
Kruszyniany memiliki kubah mini dan ruangan untuk jamaah laki-laki dan
jamaah perempuan di bagian belakang. Masjid ini juga memiliki mimbar dan
mihrab kecil sehingga juga digunakan untuk ibadah shalat Jumat.
Lingkungan Tatar di Bohiniki juga dilengkapi makam khusus untuk Muslim
yang terletak sekitar 400 meter dari masjid. Makam ini diperkirakan sudah
digunakan sejak abad ke-18. Sebagian makam hanya ditandai batu-batu
agak besar tanpa nama orang yang dimakamkan di sana. Sedangkan
kuburan untuk masa pasca-Perang Dunia II, kelihatan lebih „wah‟ yang
hampir sepenuhnya ditutup dengan batu pualam beserta nisan yang
dilengkapi dua kalimah syahadah dan nama almarhum atau almarhumah.
Kompleks pemakaman ini terlihat terawat dan bersih. Cukup banyak di atas
kuburan terdapat ikatan bunga yang masih segar. Kelihatannya kaum
Muslim Tatar juga baru berziarah ke makam mengikuti tradisi warga
Polandia lain yang ziarah ke kuburan dalam rangka merayakan „Hari Santo
Kudus‟ (All Holy Saints Day) yang merupakan hari libur nasional Polandia.
Komunitas Muslim Tatar terlihat merupakan masyarakat paguyuban, di
mana satu warga akrab dengan yang lain. Mereka hidup dari pertanian dan
peternakan, mulai dari kuda sampai ayam yang terlihat bergerak bebas.
Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mereka kian berkurang karena
pindah ke perkotaan.
Budaya Politik Indonesia
Tuesday, 11 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/10/netyus-budaya-politik-indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Dalam arti longgar, budaya politik (political culture) bertalian dengan
serangkaian sikap dan praktik yang dipegang oleh sejumlah orang yang
membentuk perilaku politiknya. Termasuk di dalamnya pertimbangan moral,
mitos politik, kepercayaan, dan gagasan tentang apa yang dapat membuat
sebuah masyarakat itu menjadi baik
Dengan kata lain, kebaikan buat semua adalah esensi dari budaya politik
yang sehat. Pertanyaannya untuk Indonesia sekarang, apakah budaya politik
yang sedang berlangsung pada tahun ini menyiratkan harapan untuk
kebaikan bangsa ini secara keseluruhan jika ditempatkan dalam parameter
Pancasila dan nilai-nilai luhurnya?
Jika jawabannya positif, berarti bangsa dan negara ini sudah berjalan di atas
rel yang benar. Namun, jika jawaban itu negatif, maka apa yang salah
dengan budaya politik kita? Analisis di bawah memberikan kebebasan bagi
pembaca untuk menentukan pertimbangan masing-masing.
Sebenarnya budaya politik itu lebih dikendalikan oleh kaum elite. Rakyat
biasa pada umumnya tinggal mengikuti saja, sadar atau karena bujukan
uang. Di Indonesia kontemporer, apa yang dikenal dengan politik uang
sudah bukan berita lagi. Hampir semua lini kegiatan partai plus elitenya, dan
perorangan untuk berebut posisi sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan
Daerah), empat orang pada tiap-tiap provinsi, permainan uang itu sudah
mewabah.
Jumlahnya bergantung pada isi kandung para pemain. Bohong besar jika
para pemain itu mengatakan bebas dari politik uang. Seorang politikus
berbakat dari sebuah partai ketika saya tanyakan mengapa dia gagal ke
Senayan, jawabannya polos: “Kalah uang.” Dengan demikian tuan dan puan
jangan terlalu berharap kepada mereka yang berhasil duduk menjadi
anggota DPR (pusat atau daerah) benar-benar akan menyuarakan aspirasi
rakyat. Sebagian mereka itu hanyalah mewakili isi kantongnya, baik melalui
utang atau harta pribadi bagi mereka yang kaya.
Adapun mengenai pertimbangan moral pada umumnya sudah dilumpuhkan
oleh pragmatisme politik yang konyol. Dari pantauan saya, hanyalah sedikit
sekali di antara para “wakil” itu yang benar-benar bermental patriot-
petarung untuk membela kepentingan bangsa dan negara secara
keseluruhan.
Memang ada juga bentuk pertarungan lain di Senayan, tetapi jangan salah
nilai, mereka bertarung bukan untuk kepentingan rakyat. Pertarungan
mereka hanyalah didorong oleh politik kekuasaan tanpa pertimbangan akal
sehat dan sikap adil. Mereka yang tersudut dalam pertarungan tampaknya
kehilangan keseimbangan, lalu membentuk kekuatan tandingan, sesuatu
yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Siapa yang dirugikan oleh akrobatik politik yang menyebalkan ini? Bukan
mereka karena mereka tetap digaji saban bulan yang diambilkan dari APBN.
Yang pasti celaka adalah rakyat karena kelakuan politisi Senayan itu bisa
menghambat program-program pemerintah yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang sudah sekian lama kurang
mendapat perhatian.
Di sisi lain, Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibentuk di bawah slogan
profesionalisme, dalam kenyataannya fenomena politik dagang sapi tidak
dapat dihindarkan. Politik inilah yang menyebabkan ada kekuatan moral
masyarakat sipil yang tidak punya saluran partai dianggap sebagai aksesoris
belaka. Bagi saya, semuanya ini menunjukkan bahwa peradaban politik
Indonesia yang dikembangkan masih belum naik kelas.
Budaya politik yang serbainstan dan nyaris tidak terkait dengan masa depan
bangsa dan negara harus dihentikan sekarang dan untuk selama-lamanya
jika memang Indonesia mau dibangun di atas pilar keadilan tanpa
diskriminasi. Kekuatan sipil yang secara masif telah membantu bangsa dan
negara harus diperlakukan dengan wajar dan proporsional. Tidak perlu
dimanjakan. Sebab, kekuatan ini lahir dan telah berbuat sesuatu yang
sangat strategis untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan menyantuni
manusia telantar, jauh sebelum Indonesia sebagai negara muncul ke peta
dunia.
Mengabaikan kekuatan ini sama artinya dengan membiarkan mereka
terluka, sekalipun mereka tidak akan pernah berhenti beramal untuk
kepentingan sesama. Di tengah pertarungan pragmatisme politik, seorang
negarawan tidak boleh hanyut di dalamnya. Kompas moral wajib selalu
dikedepankan sebagai acuan yang benar. Di luar itu, budaya politik
Indonesia masih akan terus digerogoti virus yang siap mengancam rasa
keadilan publik.
ISIS Menyasar Mahasiswa Al Azhar Kairo
Senin, 10 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/09/nerxok-isis-menyasar-mahasiswa-
al-azhar-kairo
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Waspada! Inilah yang bisa disimpulkan ketika membaca laporan investigasi
media As Sharq Al Awsat edisi Kamis pekan lalu, terkait aktivitas para
propagandis ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Mereka bukan hanya
merekrut para pemuda asing dari negara-negara Barat, seperti yang
menjadi perhatian dunia selama ini. Kini para kaki-tangan ISIS juga
langsung menusuk ke jantung dunia Islam: Universitas Al Azhar di Kairo,
Mesir.
Al Azhar merupakan universitas Islam tertua di dunia. Usianya lebih dari
seribu tahun (970 M) dan hingga kini terus berkembang pesat. Jumlah
mahasiswanya berkisar 323 ribu orang dari berbagai negara, termasuk
sekitar 5 ribu mahasiswa dari Indonesia. Ini belum termasuk jumlah siswa di
tingkat SD, SMP, dan SMA yang juga dikelola Al Azhar.
Universitas yang didirikan oleh Panglima Jauhar As Siqilli atas perintah
Khalifah Muiz Lidinillah dari Daulat Fatimiyah ini merupakan salah satu poros
pemikiran Islam, politik, dan ilmu-ilmu agama di dunia. Ia juga menjadi
benteng Ahli Sunnah wal Jamaah yang mempromosikan Islam sebagai
agama yang moderat, teleran, dan rahmatan lil alamim.
Sikapnya yang moderat dan toleran inilah yang kemudian bisa diterima oleh
berbagai pihak. Kini hampir semua negara yang ada umat Islamnya selalu
mengirimkan mahasiswanya untuk belajar ke Al Azhar, termasuk dari
negara-negara Barat.
Moderasi dan toleransi Al Azhar, terutama para alumni dan mahasiswanya,
kini bisa saja „terganggu‟ dengan hadirnya para propagandis ISIS. Para kaki
tangan Abu Bakar Al Baghdadi -- yang telah mendeklarasikan dirinya
sebagai khalifah di Negara Islam di Irak dan Suriah ini --, menurut laporan
media berbahasa Arab yang bermarkas di London, Al Sharq Al Awsat,
muncul di berbagai kawasan yang jadi tempat aktivitas mahasiswa Al
Azhar. Mereka mengendap-endap bagaikan hantu mencari mangsa.
Kawasan Husein, Kairo, adalah salah satunya. Terutama di Masjid Al Azhar
dan Masjid Husein yang berada di kawasan itu. Dua masjid ini posisinya
berseberangan dan tidak jauh dari kantor pusat Al Azhar dan kampus Al
Azhar.
Berikut adalah percakapan singkat di halaman Masjid Al Azhar antara
seseorang yang diperkirakan propagandis ISIS dan „calon mangsanya‟ yang
sempat direkam Al Sharq Al Awsat.
„„Assalamu „alaikum... Perkenalkan, nama saya Ahmad, saudaramu sesama
Muslim. Bolehkah saya berkenalan dengan Anda?‟‟
„„Nama saya Muhammad. Saya belajar di Universitas Al Azhar.‟‟
„„Anda sering datang ke Masjid Al Azhar ini?‟‟
„‟Ya...‟‟
„‟Baiklah, kita bertemu lagi pada waktu yang lain, untuk membela dan
menegakkan agama Islam di muka bumi.‟‟
Seorang yang mengaku bernama Ahmad diduga merupakan propagandis
ISIS. Yang seorang lagi adalah mahasiswa dari Mali yang baru saja
mengikuti pelajaran tambahan di bidang fikih di Masjid Al Azhar.
Menurut investigasi Al Sharq Al Awsat, bila „si mangsa‟ dianggap tak
berkenan, sang propagandis pun menghilang. Namun, bila „si mangsa‟
terlihat menyambut baik maka percakapan akan dilanjutkan di waktu lain.
Bisa melalui pertemuan langsung atau lewat media sosial (facebook, twitter,
dll). Pertemuan atau pembicaraan lanjutan ini bisa saja sampai pada
kesepakatan bagaimana cara dan ditail „si mangsa‟ bisa mencapai Irak atau
Suriah melalui jalan-jalan tikus perbatasan Turki-Suriah.
Selain Masjid Al Azhar, para propagandis Al Baghdadi juga banyak mencari
mangsa di Masjid Husein yang berada di seberang Masjid Al Azhar.
Sasarannya kali ini para pemuda yang kuliah di Al Azhar, baik mahasiswa
Mesir maupun asing. Atau para pemuda Mesir pengangguran yang
„menginap‟ di Masjid Husein.
Al Sharq Al Awsat tidak menjelaskan apakah para propagandis ISIS itu
warga Mesir atau orang asing. Di kawasan Husein bercampur baur manusia
dari berbagai bangsa. Selain terdapat Masjid Husein, Masjid Al Azhar,
kampus Al Azhar, dan kantor pusat Al Azhar, juga terdapat pasar dan jalan
memanjang yang di kanan kirinya bejejer toko-toko penjual berbagai
souvenir khas Mesir.
Namun, berdasarkan sumber intelijen Mesir, di antara para propagandis itu
terdapat orang-orang asing dari berbagai negara yang menyamar sebagai
mahasiswa Universitas Al Azhar. Mereka tinggal di asrama mahasiswa yang
bernama Islamic Student City (Madinatul Bu‟uts Al Islamiyah) di kawasan Al
„Abbasiyah, sekitar 6 km dari kampus Al Azhar. Sekitar 4 ribu mahasiswa
asing tinggal dan berbaur di asrama mahasiswa ini, termasuk mahasiswa
dari Indonesia.
Menurut Al Sharq Al Awsat, mengutip sumber tidak resmi, orang-orang Mesir
yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah berjumlah sekitar seribu
orang. Sedang sumber kemanan Mesir menyebut jumlah 8 ribu orang telah
menjadi anggota ISIS, Alqaida, dan organisasi garis keras lainnya di
sejumlah negara Arab.
Di antara jumlah tersebut bahkan ada yang menjadi pemimpin organisasi
radikal ini, seperti Aiman Al Zawahiri yang menjadi orang nomor satu di
Alqaida, menggantikan Usamah bin Ladin yang telah dibunuh pasukan AS.
Juga empat „ulama‟ Mesir yang kini menjadi referensi hukum atau undang-
undang ISIS.
Mereka adalah Hilmi Hasyim dengan nama alias Syakir Ni‟amullah, Abu
Muslim Al Misri (hakim agung ISIS), Abu Al Haris Al Misri, dan Abu Syu‟aib.
Fatwa-fatwa empat „ulama‟ dari Mesir inilah yang dijadikan dasar hukum
semua sepak terjang ISIS, termasuk diperbolehkannya membunuh,
menyiksa, merampas harta pihak-pihak yang dianggap musuh, dan tindakan
kekerasan lainnya. Pemenggalan kepala wartawan dan warga Barat yang
dipertontonkan di video yang dirilis ISIS juga bersumber dari fatwa-fatwa
mereka ini.
Hingga kini belum belum ada data berapa mahasiswa Indonesia di Mesir
yang telah terpincut dengan para propagandis Abu Bakar Al Baghdadi ini dan
pergi bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Sejauh ini baru Wildan
Mukhollad yang diketahui telah bergabung dengan ISIS dan tewas di Irak
ketika melakukan bom bunuh diri pada awal tahun ini. Wildan, 19 tahun,
berasal dari Lamongan, Jawa Timur, dan diketahui belajar di Dirasah Khosoh
Al Azhar sebelum berangkat ke Suriah dan Irak.
Melihat kondisi seperti itu, seperti yang pernah saya tulis dalam buku „ISIS:
Jihad atau Petualangan‟ yang baru diterbitkan oleh Penerbit Republika
(Pustaka Abdi Bangsa), saya khawatir atas pengaruh negatif ISIS dan
paham radikal lainnya pada para mahasiswa kita di Mesir dan negara-negara
Arab lainnya. Pengaruh itu bukan di kampus, tapi bisa saja didapat di luar
kuliah di universitas. Apalagi sebagian besar aktivitas mahasiswa berada di
luar kampus.
Ini bukan berari kita harus melarang anak-anak muda kita belajar di Timur
Tengah. Yang harus menjadi perhatian kita -- terutama Kedutaan Besar RI
di Mesir, Kementerian Luar Negeri dan Agama, aparat keamanan/intelijen,
DPR, dan para ulama -- adalah memantau dan membina para mahasiswa itu
agar tidak membawa pengaruh negatif/paham radikal ketika pulang ke
Indonesia.
Pahlawan dan Kita
Saturday, 08 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/07/neo60y-
pahlawan-dan-kita
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Apa itu pahlawan?
Siapakah yang pantas menyandang sebutan demikian?
Apakah seseorang harus meninggal terlebih dahulu baru bisa menjadi
pahlawan?
Apakah seseorang harus menjadi tua dulu untuk layak disebut pahlawan?
Bagaimana cara terbaik menghargai jasa pahlawan?
Namanya Mochammat Achiyat. Usianya saat itu baru menginjak 17 tahun.
Remaja ini mungkin tidak mengira tindakannya pada malam 30 Oktober
1945 telah mengubah sejarah Indonesia, dan mewarnai sejarah dunia.
Atas perannya, Brigadir Jenderal Mallaby tewas. Komandan Brigade 49
dengan kekuatan 6.000 Infanteri ini tewas hanya 5 hari setelah
menginjakkan kakinya di Surabaya.
Tewasnya sang jendral memicu kemarahan sekutu yang melancarkan
serangan lebih besar pada 10 November 1945 dan melahirkan hari pahlawan
yang kemudian diperingati setiap tahun.
Surabaya memang akhirnya jatuh, setelah beberapa minggu pertempuran,
tetapi perang di kota ini justru membuka mata sekutu bahwa kekuatan
Indonesia tidak bisa diremehkan.
Tanpa peristiwa Surabaya, mungkin sejarah tidak akan sama. Indonesia
harus menunggu lebih lama untuk mendapat pengakuan kemerdekaan.
Pertempuran di Surabaya adalah perang besar pertama bagi sekutu setelah
perang dunia ke-2 berakhir. Di mana-mana ketika sekutu datang, semua
takut dan tunduk, hanya di Surabaya mereka mendapat tantangan berat.
Lebih buruk lagi, momentum di Surabaya merupakan kekalahan pertama
dan terburuk dalam sejarah sekutu setelah menaklukkan Jerman dan
Jepang. Seluruh pasukan sekutu di Surabaya hampir disapu bersih pada
pertempuran gelombang pertama. Padahal mereka pasukan khusus yang
mempunyai spesialisasi perang kota dan persenjataan berat, dan telah
memenangkan pertempuran melawan Jepang di Birma sampai Semenanjung
Malaya, serta memenangkan perang melawan tentara Jerman di Afrika
Yang lebih memalukan, tidak hanya Mallaby, Inggris juga kehilangan satu
jendral lain, seorang penerbang, dalam pertempuran di Surabaya.
Pertempuran beberapa hari di Surabaya menewaskan prajurit dan jendral
lebih banyak dari perang tahunan di Eropa.
Achiyat, hanya satu dari ribuan pemuda Surabaya yang siap meregang
nyawa demi mempertahankan kemerdekaan.
Bung Tomo, tokoh penggerak perlawanan di Surabaya juga masih sangat
muda ketika itu. Usianya baru menginjak 25 tahun.
Apa yang dilakukan para pemuda Surabaya saat itu sudah memberikan
jawaban pada bahwa kita tidak perlu menunggu tua untuk menjadi
pahlawan.
Lalu apakah menjadi pahlawan harus menunggu kematian menjemput?
Ketika masih hidup, Bung Tomo adalah pahlawan bagi masyarakat
Surabaya, bahkan Indonesia. Ia menjadi sumber inspirasi, motivasi dan
panutan bagi banyak orang. Dengan kata lain, setiap kita mampu menjadi
pahlawan bagi masyarakat tanpa harus menunggu mati.Lalu siapakah yang
layak di sebut pahlawan?
Apakah peristiwa 10 November menjadi hari pahlawan karena jumlah
korban yang tewas?
Tidak, masih ada peristiwa lain seperti bencana alam yang menewaskan
lebih banyak korban.
Peristiwa Surabaya menjadi hari pahlawan bukan karena jumlah korban,
melainkan karena korban-korban tersebut gugur dalam rangka
memperjuangkan hak, membela kemerdekaan, dan mempertahankan
kebebasan.
Perjuangan, satu kata itu yang membuat mereka layak disebut pahlawan.
Lalu bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan?
Mengingat jasa mereka, merupakan hal paling biasa yang dilakukan.
Mendoakan, akan jauh lebih baik.
Tapi yang terbaik adalah meneladani mereka. Karena setiap kebaikan yang
kita lakukan atas inspirasi yang mereka berikan akan menjadi amal jariyah
bagi para pahlawan dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak.
Di antara semua pertanyaan di atas, sebenarnya masih tersisa pertanyaan
terpenting.
Apakah Anda ingin menjadi pahlawan?
Pejuang bagi keluarga, bagi anak dan istri?
Bagi masyarakat?
Pahlawan bagi bangsa?
Atau pahlawan bagi peradaban?
Alangkah indah jika hidup tak hanya untuk diri sendiri. Mungkin pilihan
bijak jika rakyat yang kini menikmati kemerdekaan karena jasa para
pejuang, berpikir untuk tidak sekedar mengingat pengorbanan para
pahlawan, tapi juga mulai memantaskan diri menjadi satu dari deret
mereka yang berjuang.
Mobil Amien Rais Ditembak
Jumat, 07 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/06/nemd5o-mobil-amien-rais-
ditembak
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha
Ini cerita lama. AH Nasution, sang jenderal besar, suatu kali berkisah, dalam
sebuah perbincangan di sore hari. Seusai suatu acara di istana, DN Aidit
tiba-tiba meminta berfoto bersama dirinya. Pimpinan tertinggi PKI itu
memanggil para wartawan. Esoknya, foto Nasution bersama Aidit
terpampang di halaman satu koran. Itulah perjumpaan terakhir Nasution
dengan Aidit sebelum terjadi geger besar.
"Mungkin semacam pesan. Kenang-kenangan terakhir," kata Nasution. Pada
30 September 1965 dini hari, segerombolan orang dari pasukan Cakrabirawa
menggeruduk rumah Nasution di Jalan Teuku Umar-lebih tepat rumah milik
mertuanya karena sampai akhir hayatnya ia tak memiliki rumah sendiri.
Mereka memberondongkan tembakan. Nasution diminta kabur oleh istrinya,
Johana Sunarti. Malang tak dapat ditolak, anaknya, Ade Irma (5 tahun),
gugur dalam gendongan.
Cerita ini memang tak simetris. Namun, wajah teror mulai menggelayut.
Pada Kamis (6/11) dini hari, diduga dua orang berboncengan sepeda motor.
Mereka menembakkan senjata dan mengenai mobil milik M Amien Rais.
Sejak reformasi, Amien mengaku sudah tiga kali mendapat teror.
Sebelumnya, dua kali kaca mobilnya dilempar batu. Namun, baru kali ini ada
teror dengan senjata berapi. Amien adalah figur seksi untuk dijadikan
target. Perannya yang cenderung antagonis memudahkan dirinya untuk
dijadikan objek permusuhan.
Hingga kini belum bisa dipastikan siapa pelaku penembakan tersebut. Kita
juga tak bisa sembarang berspekulasi ihwal motif di baliknya. Pelakunya bisa
siapa saja. Bisa saja ini terdesain. Ada orang yang mengail di air keruh,
menciptakan iklim adu domba. Atau, ada orang yang ingin membangun efek
takut pada Amien maupun PAN.
Tak pelak, peristiwa ini mengingatkan peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Amien disebut pernah berjanji, jika Jokowi menang pilpres, Amien akan
berjalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Jokowi ternyata menang. Maka ada
orang dari Malang, Giman, yang mengajak Amien untuk jalan kaki bersama
menuju Jakarta. Giman menyambangi rumah Amien, tapi tuan rumah tak
ada di tempat.
Tak hanya itu, sejumlah orang melakukan ruwatan di depan rumah Amien.
Pada titik ini mulai muncul perlawanan. Sejumlah aktivis organisasi
kepemudaan Muhammadiyah melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan
penghinaan, fitnah, dan menciptakan rasa benci serta permusuhan.
Hingga kini belum ada kejelasan kelanjutan pengaduan dari IMM, IPM, PM,
dan Kokam. Apakah kasus penembakan kali ini masih satu rangkaian
dengan dua peristiwa itu? Kita tunggu hasil penyelidikan dan penyidikan
polisi.
Saya sendiri ragu polisi akan menuntaskan kasus ini. Yang pasti, kasus
penembakan ini telah menimbulkan reaksi dari aktivis Muhammadiyah,
bukan hanya PAN. Amien adalah tokoh Muhammadiyah. Ia pernah menjadi
ketua umum ormas keagamaan ini.
Di Koalisi Merah Putih (KMP), Amien Rais hanyalah salah satu tokoh saja. Di
sini ada figur Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan
Hidayat Nur Wahid. Figur sentralnya adalah Prabowo karena dia
pengantinnya dan dari partai terbesar kedua di koalisi ini.
Namun, Amien justru yang menjadi sasaran tembaknya. Dia memang yang
tertua, dia juga gemar diwawancara. Pernyataannya artikulatif, tak jarang
bernada sengit. Peran antagonisnya di masa lalu menjadikan Amien mudah
dijadikan musuh bersama. Dialah lokomotif gerakan reformasi. Dia berada di
baris depan melawan rezim Soeharto. Ia pula yang menggagas Poros
Tengah yang berhasil mempresidenkan Gus Dur dengan mengalahkan
Megawati Soekarnoputri sang pemenang pemilu. Namun, Amien pula yang
memiliki peran tak kecil dalam melengserkan Gus Dur dan menaikkan
Megawati untuk menjadi presiden.
Di masa lalu, Muhammadiyah lekat dengan Masyumi. Partai ini memiliki
sejarah perseteruan panjang dengan PNI dan Bung Karno. Perseteruan itu
seolah dibawa terus hingga di era Reformasi, walaupun pada Pilpres 2014
Din Syamsuddin, yang merupakan ketua umum Muhammadiyah, ada
kecenderungan mendukung Jokowi. Karena itu, ia berhasil memasukkan
satu nama untuk menjadi menteri, yaitu Nila Moeloek. Namun PAN, partai
yang didirikan dengan restu resmi dari Muhammadiyah, justru mendukung
Prabowo. Amien adalah pendiri, mantan ketua umum, dan kini ketua Majelis
Pertimbangan Partai PAN.
Perseteruan pendukung Jokowi dan Prabowo hingga kini belum berakhir
benar. Di parlemen muncul pimpinan DPR tandingan-setelah KMP menguasai
pimpinan DPR dan pimpinan komisi serta badan-badan lain di DPR. Di media
sosial, perseteruan itu juga masih sering muncul.
Karena itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang mendukung Jokowi, kecewa.
Mereka berharap di lembaga wakil rakyat ini mereka ikut diberi tempat. Dari
64 posisi, mereka hanya meminta 16 posisi saja. Namun, tuntutan itu tak
dipenuhi. KIH pun membuat “lelucon serius”, membentuk pimpinan DPR
tandingan.
Sebetulnya, Jokowi dan Prabowo mengusung tema yang sama: kemandirian,
kedaulatan, pemerataan, dan nasionalisme. Yang membedakan mereka
adalah langgam politik, aktor politik, basis dan akar sosial pendukungnya,
serta para penyandang dananya.
Hal ini, misalnya, sangat berbeda dengan persaingan Demokrat dan Republik
di Amerika Serikat atau Liberal dan Buruh di Australia. Mereka memiliki visi
yang berbeda. Karena itu, siapa pun yang menang-Jokowi atau Prabowo-
adalah kemenangan kaum nasionalis. Ini akan banyak mengubah lanskap
Indonesia ke depan karena berbeda dengan masa Orde Baru maupun masa
SBY.
Semua pihak harus menanggalkan sentimen masa pilpres dan bergerak
maju menuju cita-cita. Saat ini Indonesia sedang memasuki periode emas.
Indonesia sedang memasuki masa surplus demografi yang banyak
membawa keuntungan. Peta geoplitik dan geoekonomi juga sedang berada
di Asia Pasifik. Momentum seperti ini tak datang dua kali. Dalam periode ini,
Indonesia akan menghadapi pilihan untuk mewujudkan revolusi sosial dan
revolusi ekonomi atau kita terjebak pada oligarki elite di segala bidang.
Kita harus mengawal pemerintahan Jokowi agar tetap di visi awal. Jangan
biarkan dia dibajak kaum komprador dan dikendalikan elite politik maupun
para penyandang dana. Pertarungan politik sudah selesai. Pertarungan
sesungguhnya ada di level ekonomi.
Kita tahu, sebelum tragedi G30S/PKI, teror politik sering terjadi. Tokoh-
tokoh oposisi mendapat teror fisik maupun mental. Presiden Sukarno pun
berkali-kali mendapat serangan mematikan. Kita tak ingin sejarah berulang.
Masjid Cordova
Kamis, 06 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/05/neka26-masjid-cordova
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
Ingat Cordova, pastilah ingat Andalusia—Spanyol sekarang. Tapi Cordova
yang satu ini bukan terletak di Spanyol, tapi di Slovakia, Eropa Tengah.
Meski beda lokasi, hal yang pasti sama adalah keduanya terkait dengan
Islam. Walaupun demikian, Cordova Spanyol pernah menjadi simbol
kejayaan Islam di Eropa Barat, sedang Cordova, di Bratislava, Ibu Kota
Slovia, masih bakal menempuh perjuangan panjang dan sulit untuk
pengakuan eksistensial Islam dari negara.
Kulturne Centrum Cordova, pusat kebudayaan Islam Cordova, sekaligus
merupakan satu-satunya „masjid‟ di Bratislava. „Masjid‟ harus diletakkan
dalam tanda kutip karena bangunannya bukanlah masjid seperti yang biasa
dikenal. „Masjid‟ Cordova ini tidak lain adalah „apartemen‟ berlantai dua;
lantai bawah terdapat ruangan yang biasa dibuat menjadi enam shaf,
dengan masing-masing shaf bisa diisi sekitar delapan jamaah. Kemudian
ruang atas dengan sekitar empat shaf. Walhasil, dalam kalkulasi penulis
Resonansi ini ketika melaksanakan ibadah Jumat di „masjid‟ Cordova pada
akhir Oktober lalu (31/10), ruangan „masjid‟ ini nampaknya bisa
menampung sekitar 60-an jamaah.
Atas dasar kenyataan ini, menurut berbagai laporan media Eropa, Slovakia
merupakan satu-satunya negara di benua ini yang tidak memiliki masjid.
Lukas Ondercanin misalnya, dalam artikelnya “Muslim Community Believes,
Even Without Mosque‟ (The Slovak Spectator, 28 Oktober 2013)
menyatakan, Slovakia kini satu-satunya negara di Uni Eropa yang tidak
memiliki satu masjid pun.
Muhammad Safwan Hasna (44 tahun), Ketua Yayasan Islam Slovakia
(didirikan pada 1999) yang mengelola Kulturne Centrum Cordova
menyatakan kepada delegasi Dialog AntarAgama Indonesia telah cukup lama
mengajukan izin pembangunan sebuah masjid, karena lahannya sudah
tersedia di Patronka, di pinggir pusat kota Bratislava, sejak beberapa tahun
lalu.
Untuk mendapatkan izin pembangunan, harus ada persetujuan 20 ribu
warga setempat di mana masjid akan dibangun. Mereka ini umumnya adalah
penganut Katolik yang tidak selalu memiliki persepsi benar dan akurat
terhadap Islam dan kaum Muslimin. Safwan menjelaskan, pengurus Cordova
berusaha menjalin hubungan baik dengan pimpinan gereja Katolik, tetapi
tidak selalu berhasil. Masjid Cordova misalnya mengundang pimpinan gereja
dalam kesempatan iftar (berbuka puasa bersama, namun respon mereka
tidak seperti yang diharapkan.
Dengan keadaan seperti ini, tidak mudah mendapat persetujuan mereka—
apalagi untuk mendirikan masjid. Selain itu, penyebab utama tidak turunnya
izin pembangunan masjid juga terkait dengan kenyataan, belum adanya
pengakuan pemerintah Slovakia terhadap Islam sebagai agama terdaftar
yang juga dianut sebagian warganya. Sejauh ini hanya Katolik bersama
puluhan denominasi Kristianitas lain dan agama Yahudi yang telah lama
terdaftar dan dengan demikian mendapat pengakuan negara.
Populasi Muslim di Slovakia memang sedikit. Dari sekitar 5,4 juta penduduk
Slovakia, sekitar 62 persen adalah Katolik; 12 persen Protestan dan
denominasi Kristen lain. Kaum Muslim menurut Yayasan Islam berjumlah
sekitar 5.000an; sedangkan Pew Research Institute (2013) memperkirakan
sekitar 10.600 orang.
Menurut Imam Hasna, sejak abad 9 Masehi Islam sudah sampai ke Slovakia,
dibawa para pedagang. Kemudian sepanjang abad 16-17 Slovakia dikuasai
Dinasti Turki Utsmani. Merupakan wilayah dengan penganut Katolik yang
teguh, sepanjang masa ini, nampaknya tidak terjadi konversi penduduk lokal
ke dalam Islam. Karena itu, kebanyakan warga Muslim adalah keturunan
Albania dan Bosnia. Belakangan juga terdapat sejumlah Muslim asal Arab
dan Asia Selatan.
Kalangan Muslim aktivis berusaha memperkenalkan Islam dalam bahasa
Slavik, misalnya melalui majalah Islam yang pertama kali diterbitkan pada
1937. Tetapi sejak akhir Perang Dunia II, rejim komunis tidak membenarkan
keagamaan apapun. Meski demikian, pada 1972, seorang akademisi, Ivan
Hrebek menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Czech—yang juga
dipahami warga Slovakia; belakangan Hrbek dilaporkan memeluk Islam.
Meski Islam belum merupakan agama terdaftar, Imam Hasna yang hijrah
dari Syria untuk pendidikan tingginya menyatakan, kaum Muslimin Slovakia
tidaklah tertindas. Sebaliknya, mereka menikmati kebebasan yang bahkan
tidak mereka temukan di negara berpemerintahan Muslim di Timur Tengah
dan Asia Selatan.
Walaupun demikian, kaum Muslimin Slovakia bukan tidak jarang menjadi
sasaran kecurigaan pemerintah dan kalangan masyarakat lokal. Berbagai
peristiwa kekerasan dan teror yang melibatkan para pelaku Muslim,
membuat upaya mereka memperkenalkan wajah Islam yang damai sangat
sulit. Penangkapan seorang remaja laki-laki (14 tahun) di Bandara Vienna
sehari sebelumnya (30 Oktober) yang terduga membawa bom, “membuat
kami ketar-ketir”, ujar Hasna.
Hasna menyesalkan kalangan Muslim yang konon ingin „memperjuangkan‟
Islam, tetapi dengan cara-cara yang justru merusak citra Islam dan kaum
Muslimin. “Dengan tindakan seperti itu, mereka bukan menolong Islam dan
kaum Muslim, tetapi sebaliknya mencemarkan agama Allah”.
Tukang Cat Tuesday, 04 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/03/neh0m1-tukang-cat
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Sampai Sabtu, 1 November 2014, tukang cat ini telah bekerja di rumah
kami di Nogotirto, Yogyakarta, selama tiga minggu, sekalipun tidak
semuanya bisa masuk penuh. Inisialnya adalah W, M, S, dan D.
Pekerjaannya sangat rapi, tertib, dan fokus. Di antara keempatnya, M
adalah yang paling menarik. Bawaannya lucu dan ceria. Tubuhnya kurus,
rambut panjang. Saya memanggilnya seniman.
Sepeda motor Yamaha M keluaran 1977 persis sama dengan tahun
kelahirannya. Warna merah, STNK-nya sudah tidak diurus lagi. Di saat
kondisi motornya masih agak baik, pernah ditangkap polisi, lalu dibayar Rp
90 ribu. Lepas.
Tetapi setelah tua renta, masih ditangkap lagi karena pelanggaran lalu
lintas. Minta uang rokok. Karena tidak punya uang, polisi melepaskan begitu
saja. Mungkin ada rasa iba melihat sepeda yang sudah berusia hampir 40
tahun itu. Rem tangan tidak ada, kabel-kabelnya seperti berkeliaran tak
teratur, tetapi fungsional. Spionnya tanpa kaca. Katanya kecepatan tertinggi
masih sekitar 60 km per jam.
Di atas sadel sepeda tua inilah M hilir mudik sebagai pekerja harian, entah
untuk berapa lama lagi. Tetapi tuan dan puan harus bangga, mereka ini
adalah anak-anak bangsa sebagai pekerja keras dengan penghasilan UMR
(upah minimal regional).
Adapun pemberi kerja yang baik hati, pasti diberi tambahan dan bonus. M
pernah bekerja di Kalimantan dan Jakarta, sekarang tidak boleh oleh
mertuanya pergi terlalu jauh. Karena terlambat kawin, M baru punya anak
satu. Dia memang berjanji belum akan berumah tangga sampai ibunya
sembuh dari sakitnya. Adapun W, S, dan D berpenampilan kalem tetapi
kadang-kadang dengan kocak menggoda M dengan kalimat-kalimat jenaka.
Kami pun tertawa bersama. Saya menikmati bergaul dengan mereka.
Pembicaraan lepas kami tidak pernah menyinggung DPR atau anggotanya
yang angkat meja karena berseteru. Andaikan disinggung, mereka
tampaknya tidak berminat, bikin pusing kepala saja. Apalagi ada DPR
tandingan yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia
merdeka. Konsentrasi mereka adalah pada pekerjaan yang ditekuninya,
demi melangsungkan hidup berkeluarga. Disiplin kerja tukang cat ini
demikian tinggi. Saya salut pada mereka semua.
Sejak hari-hari terakhir ini, W membawa burung tacer jawa (semacam
murai) ke tempat kerja yang baru dibeli dua bulan lalu. Kicauannya yang
tanpa henti menjadi hiburan bagi mereka dalam suasana panas yang
menyengat.
Burung dengan warna hitam putih itu itu seperti tak mengenal susah,
sekalipun terkurung dalam sangkar. Kerjanya melompat ke sana kemari
sambil bernyanyi. Suaranya jauh lebih merdu dibandingkan nyanyian
sumbang sebagian anggota DPR dalam suasana peradaban politiknya yang
masih rendah. Kicauan burung adalah untuk hiburan pendengarnya, suara
anggota DPR yang lantang tetapi culas menyakitkan telinga rakyat.
Sesekali para tukang ini saya ajak makan siang bersama dengan suguhan
gulai dan satai kambing masakan Jawa yang terkenal. M tidak ikut, takut
kepalanya terganggu. Bisa pening katanya. Ke warung Padang, dia mau
sekali. Semuanya tidak ada yang pantang.
Makan bersama dengan para tukang ini sungguh menyenangkan.
Suasananya egaliter, tanpa ada sekat sama sekali. Sebagai anak kampung,
saya adalah bagian dari mereka. Tetapi, saya tidak kuat bekerja fisik seperti
mereka yang tahan banting itu. Mereka mesti disapa dan disantuni dalam
batas-batas kemampuan kita.
Tanpa mereka, banyak sekali keperluan hidup ini yang akan terbengkalai.
Para pekerja adalah tiang ekonomi yang sangat vital bagi desa dan kota.
Jika mereka bekerja dengan penuh keceriaan, itu adalah pertanda mereka
senang. Panas terik seperti dibawa lalu saja, karena hatinya gembira. Maka
adalah sebuah kemuliaan sekiranya bos-bos besar perusahaan menyapa
para pekerjanya dengan sapaan kemanusiaan yang tulus yang dapat
mempertalikan hati dengan hati. Semoga demikian!
Bravo Swedia!
Senin, 03 November 2014, 16:32 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/03/negiik-bravo-swedia
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Awal Oktober lalu masyarakat internasional dikejutkan dengan pengumuman
Swedia yang akan segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara
merdeka dan berdaulat. Pengumuman itu disampaikan Stefan Lofven dalam
pidato pelantikannya sebagai Perdana Menteri (PM) Swedia yang baru di
depan parlemen pada 3 Oktober 2014. Lofven menggantikan PM
sebelumnya, Fredrik Reinfeldt, yang telah berkuasa selama delapan tahun.
Keterkejutan masyarakat internasional itu lantaran „tidak ada angin dan
tidak ada hujan‟ tiba-tiba Sang PM Swedia yang baru dilantik itu mendukung
penuh terhadap Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Apalagi ia
tak sedang mengumbar janji-janji pemilu. Keterkejutan yang kemudian
mengundang pertanyaan atau tepatnya keraguan, apakah pengumuman itu
benar-benar akan dilaksanakan?
Pertama, sebagai negara anggota Uni Eropa, politik luar negeri Swedia tentu
akan segaris lurus dengan negara-negara Eropa lainnya, atau minimal
sehaluan dengan negara-negara Eropa Barat yang selama ini mempunyai
pengaruh besar terhadap stabilitas di kawasan Timur Tengah. Dalam hal
konflik Israel-Palestina, negara-negara Eropa pada umumnya cenderung
mendukung kepentingan negara dan bangsa Israel.
Kedua, selama ini peran Amerika Serikat (AS) dan masyarakat Zionis
internasional sangat kuat mempengaruhi politik luar negeri Uni Eropa,
terutama terhadap negara-negara di Timur Tengah. Ketiga, Swedia boleh
dikatakan tidak mempunyai kepentingan yang berarti dengan negara-negara
Arab. Sebagai misal, Swedia merupakan negara yang paling minim
mengambil keuntungan ekonomi dalam hubungannya dengan dunia Arab
dibadingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara Arab tidak
termasuk 10 besar patner bisnis Swedia.
Keempat, di Swedia tidak ada masyarakat Arab yang bisa memberi
pengaruh atau kekuatan menekan kepada pemerintah negara itu. Kelima,
Swedia termasuk negara kaya. Jumlah penduduknya hanya sepertiga
keseluruhan warga Arab Saudi, namun besaran APBN kedua negara hampir
sama. Dengan begitu ia tidak perlu bantuan dari negara lain, terutama dari
negara-negara Arab.
Karena itu, ketika Swedia -- lewat menteri luar negerinya, Margot Wallstrom
-- pada 30 Oktober lalu benar-benar mengakui kemerdekaan dan kedaulatan
negara Palestina, kita pun perlu mengacungkan jempol, seraya
meneriakkan, „‟Bravo Swedia!‟‟
Menurut Wallstrom, pengakuan resmi negaranya terhadap kemerdekaan dan
kedaulatan negara Palestina merupakan sumbangan bagi masa depan yang
lebih baik di kawasan yang telah lama diwarnai kehancuran dan frustasi. Ia
mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina karena mereka telah
memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara berdasarkan hukum
internasional. Yaitu: ada wilayah, rakyat, dan pemerintah.
Wallstrom menolak reaksi AS yang mengatakan sikap negaranya terlalu
cepat. Sebaliknya, ia justeru menegaskan pengakuan terhadap
kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina sudah sangat terlambat.
Karena itu, Wallstrom pun berharap sikap negaranya akan diikuti oleh
negara-negara Eropa lainnya.
Sebelum pengakuan ini pun, Swedia sebenarnya telah menunjukkan
pembelaannya terhadap nasib bangsa Palestina. Salah seorang perdana
menterinya, Sven Olof Joachim Palme (30 Januari 1927-28 Februari 1986),
beberapa kali mengecam kebiadaban Zionis Israel terhadap bangsa
Palestina. Ia pun tewas ditembak menjelang tengah malam pada 28 Februari
1986.
Kini Swedia telah melangkah lebih jauh lagi, yaitu mengakui secara resmi
kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Pengakuan ini jelas merupakan
peringatan keras kepada PM Israel Benjamin Netanyahu, bahwa para
pemimpin dunia yang „waras dan mempunyai hari nurani„ seperti halnya PM
Swedia Stefan Lofven akan selalu menentang kesewenang-wenangan Zionis
Israel. Pemimpin seperti Lofven tidak akan bisa ditekan oleh siapa pun,
termasuk intimidasi yang sering dilakukan oleh lobi-lobi Zionis
internasional.
Sejauh ini Swedia merupakan negara maju pertama anggota Uni Eropa yang
mengakui kemerdekaan Palestina. Sedangkan negara lain di Eropa yang
sudah mengakui kemerdekaan Palestina adalah Islandia, Malta, dan Siprus.
Namun, ketiga negara ini merupakan negara kecil yang tidak banyak
pengaruhnya dalam percaturan politik dunia.
Kini Swedia masuk dalam jajaran 135 negara yang telah mengakui
kemerdekaan Palestina. Pengakuan yang diharapkan bisa segera
merealisasikan kemerdekaan Palestina yang berdaulat di wilayah Tepi Barat
dan Gaza. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Palestina ini juga
sekaligus sebagai kekuatan penekan kepada Israel untuk segera mengakui
negara Palestina.
Tanpa pengakuan terhadap negara Palestina, PM Benjamin Netanyahu dan
penguasa Israel selanjutnya akan terus menjajah wilayah Palestina dan
menjadikannya sebagai bagian dari Israel. Watak bangsa Israel yang
ekspansionis hanya bisa diberhentikan dengan kekuatan besar dari
masyarakat internasional. Pengakuan internasional ini sekaligus
membuktikan bahwa Negara Palestina betul-betul ada dan eksis di muka
bumi, sehingga Zionis Israel tidak bisa berbuat semena-mena terhadap
bangsa dan negara Palestina.
Bila mereka terus menjajah dan tidak mengakui kemerdekaan Palestina,
maka mereka akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat internasional.
Inilah arti penting dari pengakuan Swedia dan bangsa-bangsa waras lainnya
terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Sekali lagi, bravo Swedia!
Sumpah Pemuda dan Bola Indonesia
Sabtu, 01 November 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/31/neb6a4-sumpah-pemuda-dan-bola-
indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Bukan harapan semu jika bangsa Indonesia menaruh harapan agar tim
sepak bola U-19 bisa sampai ke jenjang tertinggi Piala Dunia U-20. Harapan
ini tentu saja beralasan karena kesebelasan yang dilakoni pemuda Indonesia
ini sudah pernah mengukir sejarah dengan meraih juara AFF U-19 tahun
2013.
Tidak hanya mencapai juara, asuhan Indra Sjafri ini bahkan berhasil
memecah kebuntuan prestasi Indonesia di ajang sepak bola. Puasa gelar
selama lebih dari 22 tahun bagi Indonesia telah diakhiri Evan Dimas dan
kawan-kawan.
Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Tim U-19 harus bertekuk lutut dalam
babak kualifikasi tanpa memperoleh kemenangan sekali pun. Hilang sudah
harapan Indonesia? Tidak, Indonesia tidak hilang harapan. Tanah Air
tercinta masih punya banyak kesempatan.
Timnas U-19 mungkin tidak berhasil menembus U-20 tahun depan, tetapi
masih ada banyak kompetisi lain yang bisa mereka lakoni. Selain itu tak
terhitung generasi muda yang meniti karier dan ingin berprestasi juga
seperti mereka.
Potensi anak muda di Indonesia begitu banyak. Masalahnya seberapa kita
memberi jalan bagi mereka?
Saya teringat ketika Juventus datang ke Indonesia. Tidak main-main, tim
juara Seri A Italia tersebut mendatangkan pemain-pemain super sekelas
Pirlo, Buffon, dan lain-lain yang sudah malang melintang di dunia sepak bola
internasional.
Kalau ada yang kemudian saya sayangkan atas kedatangan mereka adalah
mengapa bukan U-19 yang diturunkan untuk menghadapi? Jika bukan
timnas senior, U-19 adalah lawan paling tepat untuk kepentingan masa
depan sepak bola di Tanah Air.
Alih alih mereka, justru saat itu orang asing yang bermain di Indonesia yang
mendapat kesempatan emas bertanding melawan Juventus. Ketika gawang
Buffon dijebol dalam waktu teramat singkat, sejarah tersebut tidak diukir
bangsa Indonesia melainkan pemain asing yang sedang bermain di
Indonesia.
Sayang sekali, peluang sedemikian berharga sebagian justru diberikan
kepada pihak asing. Padahal anak bangsa begitu dahaga atas kesempatan
serupa. Bermain dengan tim papan atas Eropa jelas merupakan pengalaman
langka.
Karena itu saya sangat mengerti ketika sang pelatih membawa U-19 ke
Spanyol. Hanya saja di sana mereka tidak bisa bertemu pemain senior kelas
A, hanya kelas B atau bahkan C, sebab memang sangat sulit untuk bisa
bertanding dengan tim kelas A di Eropa.
Kejadian ini kembali mengantarkan saya pada penyesalan, sekali lagi,
mengapa kedatangan Juventus tidak diberikan pada timnas atau U-19 atau
setidaknya untuk anak bangsa.
Sementara menilik ke belakang, pemuda Indonesia adalah bangsa yang
mempunyai darah kepeloporan. Sumpah Pemuda, misalnya, dicanangkan
oleh pemuda di Tanah Air yang usianya tidak jauh berbeda dengan para
pemain U-19. Usia para penyelenggara Sumpah Pemuda ketika itu bervariasi
antara 19 hingga 30 tahunan.
Bahkan buku "Gara-Gara Indonesia" karya Agung Pribadi mengungkapkan,
salah satu peserta kongres dari Jong Sulawesi, Johanna Tumbuan, masih
berusia 18 tahun ketika mengikuti. Sama dengan usia rata-rata anggota
timnas U-19, generasi muda yang punya semangat mengharumkan nama
bangsa. Mereka sudah membuktikan dan masih punya kesempatan lagi
untuk membuktikan. Di bawah U-19 masih banyak remaja dan anak-anak
yang juga ingin mengharumkan nama Indonesia melalui sepak bola.
Tidak berhenti di sepak bola, sebagian anak muda berjuang mengharumkan
nama bangsa di Asian Games yang baru saja berlalu. Beberapa keping
medali emas berhasil dibawa pulang, juga perak dan perunggu.
Prestasi yang sangat membanggakan, tapi tidak disambut antusias segenap
bangsa. Tidak ada antusiasme ketika mereka pulang, tidak ada sambutan
gegap gempita, tidak banyak pemberitaan. Seolah tidak ada bedanya
mereka pulang dengan menyabet emas atau tanpa apa-apa. Miris.
Seharusnya seluruh lapisan memberi apresiasi yang pantas bagi perjuangan
anak-anak muda di Tanah Air. Juga membuka sebanyak-banyaknya
kesempatan atas berbagai peluang yang ada. Prestasi yang menurun bisa
jadi merupakan teguran untuk bangsa.
Tugas segenap pihak di Tanah Air untuk terus memberi dukungan penuh
atas segala usaha dan jerih payah pemuda kita demi menjadikan Indonesia
bercahaya, hingga mereka tahu mereka tak sendiri berjuang.
Kabinet Kerja Keras
Friday, 31 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/30/ne9ma2-kabinet-kerja-keras
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha
Hari itu, Rabu (22/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar jumpa
pers di halaman belakang Istana Merdeka. Di bawah pohon trembesi. Inilah
jumpa pers perdana. Jumpa pers yang ganjil. Ia tidak didampingi Wakil
Presiden Jusuf Kalla.
Saat itu, publik sedang menunggu pengumuman susunan kabinet. Jokowi
hanya menyebutkan bahwa ada delapan nama calon menteri yang masuk
daftar merah KPK dan PPATK sehingga pengumuman kabinet belum bisa
dilakukan. Namun, ada satu hal yang menarik dalam jumpa pers yang
sangat singkat itu, Presiden didampingi Panglima TNI, tiga kepala staf
angkatan, Kepala Polri, dan Kepala BIN. Bahkan, Panglima TNI dan KSAD
mengenakan baret.
Hari itu memang ada eskalasi politik di sekitar kekuasaan. Muncul beragam
rumor. Para wartawan yang bertugas di istana, pada sore harinya, bahkan
bergerak ke Tanjung Priok. Mereka dalam koordinasi istana. Pasukan
Pengamanan Presiden juga bersiap-siap. Panggung dan tata cahaya
disiapkan. Katanya, akan ada pengumuman susunan kabinet pada malam
itu.
Rumor berseliweran. Sehari sebelumnya, Wapres bertemu pemimpin oposisi
Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra. Wapres juga bertemu Aburizal
Bakrie, ketua umum Golkar, dua hari berikutnya. Di lingkungan PDIP dan
seputar Megawati Soekarnoputri juga ada dinamika.
Dinamika yang sama terjadi di partai pengusung lainnya. Tentu saja,
kelompok-kelompok kepentingan yang berada dalam barisan pendukung
Jokowi-JK juga ikut ramai. Sesuatu yang wajar. Mereka sedang bertarung
dalam perebutan kursi di kabinet. Drama yang cukup panjang, bahkan
cenderung panas.
Akhirnya, pada Ahad (26/10) sore, Presiden mengumumkan susunan
kabinet. Ada 34 menteri. Sama dengan jumlah menteri era SBY periode
kedua. Reaksi pasar dan publik relatif datar terhadap susunan kabinet. Tidak
jelek, tapi juga tidak bagus-bagus amat. Sebuah reaksi yang spontan.
Tentang kualitas yang sesungguhnya hanya bisa dibuktikan oleh kinerja.
Kita butuh waktu untuk menilai dengan objektif. Beri kesempatan kepada
mereka untuk bekerja.
Paling banter kita hanya pada taraf menilai berdasarkan statistik dan hal-hal
yang sifatnya kasat mata. Ada menteri-menteri yang ditempatkan tak sesuai
keahliannya, bahkan cenderung 'tertukar' --mirip judul serial sinetron “Putri
yang Ditukar”.
Kehadiran Ryamizard Ryacudu (kelahiran 1950) sebagai menteri pertahanan
yang lebih senior dari Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno (kelahiran
1952) merupakan catatan tersendiri. Jumlah menteri perempuan merupakan
yang terbanyak dalam sejarah, sebuah pertanda bagus. Latar belakang sipil-
militer, agama, persebaran usia, latar belakang pendidikan (kecuali
kehadiran Susi Pudjiastuti), dan persebaran provinsi relatif sama dengan
susunan menteri kabinet SBY yang kedua. Relatif lambatnya pengumuman
menunjukkan tak mudahnya Jokowi menyusun kabinet. Ini karena Jokowi
bukan figur sentral di partainya.
Tim ekonomi terlihat tak begitu solid. Ada terlalu banyak warna. Visi Trisakti
tak begitu menonjol. Bahkan, ada menteri yang masuk kategori neolib,
sebuah pandangan ekonomi yang berseberangan dengan Trisakti yang
menjadi ideologi PDIP.
Selain itu, ada menteri-menteri yang di lapangan bisa masuk dalam satu
rangkaian dalam proses perizinan, tapi berasal dari partai yang sama. Hal ini
sangat berbahaya, rawan vested interest, dan tak menciptakan
mekanisme checks and balances. Duduknya orang-orang partai di
kementerian-kementerian tertentu juga mengundang kecurigaan ada
agenda kepartaian.
Alotnya penyusunan kabinet juga bukan semata faktor pertarungan partai di
pemerintahan, melainkan juga karena hadirnya kelompok-kelompok
kepentingan. Duduknya orang-orang itu di pemerintahan, pada akhirnya, tak
lepas dari siapa pengusulnya-mirip oligarki.
Yang paling menonjol dari kabinet ini adalah hadirnya figur-figur gila kerja
(workaholic), seperti Susi Pudjiastuti (menteri kelautan dan perikanan),
Rudiantara (menkominfo), Ignasius Jonan (menhub), Anies Baswedan
(menteri kebudayaan pendidikan dasar dan menengah), dan Siti Nurbaya
(menteri lingkungan hidup dan kehutanan). Kita berharap masih ada figur-
figur lain yang pekerja keras seperti mereka-kita masih butuh informasi lagi
soal ini.
Hal ini sesuai dengan nama kabinet yang diumumkan Jokowi: Kabinet Kerja.
Nama ini meleset dari perkiraan sebelumnya bahwa kemungkinan bernama
Kabinet Trisakti. Namun, dua nama ini sama-sama dinisbahkan pada Bung
Karno. Kabinet Kerja adalah nama yang digunakan Bung Karno dalam masa
Demokrasi Terpimpin, mulai 1959. Tiga kabinet kerja (I, II, dan III) dipimpin
Djuanda Kartawidjaja, sedangkan Kabinet Kerja IV dipimpin Subandrio.
Bung Karno menamakan kabinet kerja karena dipimpin oleh profesional dan
umumnya berisi orang-orang nonpartai.
Kehadiran figur-figur pekerja keras akan menjadi warna pemerintahan
Jokowi. Mereka akan lari cepat, birokrasi harus mengikuti irama sang
menteri. Mereka akan fokus pada target. Mirip dengan cara kerja institusi
bisnis. Kata-kata Jokowi saat mengenalkan menteri untuk “berlari” menuju
barisan merupakan sinyal kuat soal itu.
Perbedaan politik, visi pembangunan, bahkan pertarungan saat penyusunan
kabinet diharapkan akan tenggelam oleh capaian-capaian kinerja para
menteri. Figur-figur pekerja keras juga biasanya akan pragmatis dan
moderat selama tak mengganggu target. Hal ini akan mengurangi friksi
dengan parlemen, yang kali ini dikuasai oposisi.
Asal mereka tak terpeleset pada komunikasi politik, tak tersandung
birokrasi, dan bisa menghindar dari aspek personalitas yang negatif, maka
kabinet ini akan sesuai namanya, yaitu Kabinet Kerja. Kita lihat dalam tiga
bulan ke depan, setelah itu baru kita memberikan penilaian.
Kajian Islam CUHK (1) Kamis, 23 Oktober 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/22/ndurfj-kajian-islam-cuhk-1
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
Sino-Islamic cultural sphere, ranah budaya Islam Cina yang secara
sederhana mencakup seluruh kawasan Asia Timur, dalam kerangka yang
saya bangun, adalah salah satu dari delapan ranah budaya Islam secara
keseluruhan. Tujuh ranah budaya Islam lain: Nusantara (Asia Tenggara),
Anak Benua India, Persia (Iran), Arab, Turki, Afrika Hitam (Sub-Sahara
Afrika), dan belahan dunia Barat (Western hemisphere).
Setiap ranah budaya Islam memiliki distingsi sendiri dalam ekspresi sosial,
budaya dan politik, dan pengamalan keislaman. Karakter dan distingsi ranah
budaya Sino-Islamic menjadi subjek pembicaraan penulis “Resonansi” ini
dalam ceramah di Chinese University of Hong Kong (CUHK) pada 8 Oktober
2014 lalu.
Distingsi itu, misalnya, paling terlihat jelas dalam arsitektur masjid khas
Cina berwarna merah yang bukan tidak mirip “kelenteng”. Ceramah agama,
khutbah Jumat, bacaan al-Fatihah, dan doa dalam bahasa Arab ketika shalat
terasa kental dengan aksen vernakular-bahasa lokal.
Lebih jauh, kolega saya dari Universitas Hawaii, Profesor Dru Gladney, yang
merupakan salah satu pakar paling terkemuka tentang Islam Cina,
menyatakan, pusat sosial-keagamaan Muslim Cina selain masjid adalah
kuburan pendahulu. Hal terakhir ini terkait dengan tradisi budaya
masyarakat Cina secara keseluruhan yang sangat menghormati para leluhur.
Sejarah dan tradisi Sino-Islamic sangat panjang. Kaum Muslimin Cina
daratan (mainland) memiliki “ingatan bersama” (collective memory), Islam
sudah menyebar dan berakar kuat di Kanton (kini Guangzhou) dan Pulau
Hainan sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi.
Menurut mereka, Islam dibawa seorang “Saad” yang konon sahabat Nabi
Muhammad. Beberapa waktu lalu saya pernah bertanya kepada pemimpin
Muslim di Guangzhou dan Xi'an, apakah “Saad” itu adalah Saad ibn Abi
Waqqas, mereka tidak bisa menjawab atau memastikannya.
Adanya eksistensi Sino-Islamic sejak abad ke-8 Masehi tampaknya menjadi
dasar bagi munculnya teori Slamet Muljana dalam “Runtuhnya Kerajaan
Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam Nusantara” (1968) bahwa
sedikitnya enam orang Wali Songo adalah keturunan ulama Cina. Sebagai
konsekuensinya, Islam Indonesia juga berasal dari Cina. Ia juga
berpandapat, pendiri dan beberapa raja Kerajaan Demak adalah Muslim
keturunan Cina.
Teori Slamet Muljana jelas sangat kontroversial dan karena itu ditolak
banyak sejarawan dan ahli sejarah Islam Indonesia seperti Profesor HAMKA.
Memegangi teori tentang asal usul Islam Indonesia dari Mesir, HAMKA
menolak teori Slamet Muljana. Di tengah suasana masih kuatnya sentimen
anti-Cina-terkait G30S/PKI yang dihubungkan dengan Republik Rakyat Cina
(RRC), pemerintah Orde Baru melarang penerbitan dan pengedaran buku
tersebut.
Bagi penulis “Resonansi” ini yang memperkenalkan teori “mata air” tentang
asal usul Islam Nusantara, sangat boleh jadi Islam juga datang dari Cina-
sebagai sebuah “mata air”. Hal ini sama halnya dengan adanya “mata air”
lain seperti Kelantan, Benggali, Persia, dan Mesir. Tetapi, “mata air” paling
besar adalah dari Arabia yang mencakup Irak, Yaman, sampai Makkah dan
Madinah.
Jadi, dengan adanya sejumlah bukti tentang hubungan Islam Cina dengan
Islam Nusantara, bukan tidak mungkin sebagian penyiar Islam juga datang
dari wilayah Cina ke Nusantara. Hal sangat mungkin karena adanya
hubungan pelayaran dan kehadiran pengembara Cina seperti Laksamana
[Muhammad] Cheng Ho di sejumlah pelabuhan di kepulauan Nusantara.
Dengan adanya wilayah dan tradisi Sino-Islamic yang begitu panjang,
penulis “Resonansi” ini dalam ceramah dan diskusi di CUHK berpendapat,
pembentukan Islamic studies di universitas ini sangat tepat. Selain itu,
perkembangan dan dinamika Islam, baik di Hong Kong sendiri dan wilayah
daratan Cina serta dunia internasional lebih luas, memerlukan pengetahuan
dan pemahaman lebih baik dan lebih akurat tentang Islam dan masyarakat
Muslim.
Karena itu, the Islamic Studies Initiative (ISI, Inisiatif Kajian Islam) yang
diluncurkan di CUHK pada September 2013 merupakan langkah sangat tepat
dan sudah lama ditunggu. Inisiatif ini merupakan hasil dari persetujuan
antara CUHK yang diwakili Research Institute for the Humanities (RIH CUHK)
dengan Islamic Cultural Association (ICA) Hong Kong. Pihak terakhir ini
bertanggung jawab menyediakan dana yang diperlukan untuk pembentukan
dan penguatan Kajian Islam di CUHK.
Dalam bacaan penulis “Resonansi” ini, kerja sama seperti ini agak jarang
terjadi. Pada satu pihak terdapat universitas (CUHK) yang bertumpu pada
pengajaran dan penelitian akademik ilmiah, sedangkan pada pihak lain
adalah ICA yang merupakan organisasi keagamaan, dakwah, dan sosial-
budaya Islam yang bergerak di atas ukuran normatif Islam. Dalam sejumlah
kasus lain, bukan tidak sering kedua belah pihak semacam ini sulit
dipertemukan, dan bahkan terjadi 'ketegangan'.
Kajian Islam jelas merupakan hal baru di lingkungan universitas di Hong
Kong. Subjek mengenai Islam boleh dikatakan absen dalam program
universitas. Barulah pada pertengahan dasawarsa 2000-an, subjek tentang
Islam ditambahkan ke dalam kurikulum sebagai komponen minor dalam
Kajian Agama. Meski bermula sebagai subjek “minor”, perlahan tapi pasti
Kajian Islam di Hong Kong kian menemukan momentum.
Kajian Islam CUHK (2) Thursday, 30 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/29/ne7t1z-kajian-islam-cuhk-2
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
Meski sejarah dan tradisi Sino-Islamic cultural sphere, ranah budaya Islam
Cina, khususnya di Hong Kong, telah berlangsung sangat lama, tapi Islam-
Muslimin kawasan ini tak banyak diketahui dunia luar. Memandang cukup
signifikannya jumlah kaum Muslimin Cina dan transformasi ekonomi dan
sosial-budaya yang terus berlangsung di negara ini dalam beberapa
dasawarsa terakhir, sepatutnyalah Islam-Muslimin yang merupakan bagian
integral warganya mendapat perhatian lebih intens.
Pandangan seperti ini terlihat lebih kontekstual di Hong Kong yang —karena
pernah menjadi koloni Inggris selama satu abad sampai 1997— memiliki
sejarah dan tradisi sosial-budaya dan politiknya yang khas. Eks koloni
Inggris ini lebih bebas, kosmopolitan, dan multikultural —termasuk dalam
bidang keagamaan. Karena itu pula, ekspresi Islam dan kaum Muslim dapat
lebih menemukan kebebasannya.
Dalam percakapan penulis Resonansi ini dengan beberapa Muslimah
berjilbab, misalnya, mereka mengakui tidak pernah mengalami pelecehan
(harassement karena pengungkapan identitas keislaman semacam itu.
Mereka merasakan, masyarakat dan Pemerintah Hong Kong memberikan
kebebasan beragama dan toleran dengan perbedaan.
Sejak masa pasca-Inggris yang berlanjut dengan berbagai perkembangan
pada tingkat internasional lebih luas, Islam dan kaum Muslim mendapat
perhatian lebih intens dari berbagai kalangan masyarakat Hong Kong,
khususnya para peneliti, dosen, guru, mahasiswa, dan murid. Sejak waktu
ini pula kunjungan ke masjid-masjid di Hong Kong kian meningkat karena
menjadi salah satu medium untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman
langsung tentang ajaran Islam dan berbagai aspek kehidupan Muslim.
Pada saat yang sama, khususnya sejak pertengahan 2000-an, lima dari
sembilan universitas yang ada di Hong Kong mulai menawarkan mata kuliah
untuk memberikan pengetahuan dasar tentang Islam. Selanjutnya, terlihat
peningkatan minat pada bahasa Arab dan keuangan Islam. Juga terdapat
sejumlah mata kuliah yang termasuk ke dalam antropologi, kajian agama,
ilmu sosial, dan hubungan internasional yang dalam dan satu hal membahas
Islam dan masyarakat Muslim.
Berkat peningkatan minat ini, pada 2012 buku pertama berjudul Islam in
Hong Kong: Muslims and Everyday Life in China‟s World City diterbitkan
Hong Kong University Press. Buku ini terutama membahas kehidupan
keislaman kaum muda Muslim Hong Kong. Penerbitan ini disusul buku kedua
Islam and China‟s Hong Kong: Ethnic Identity, Muslim Networks and the
New Silk Road (Routledge). Karya terakhir ini menampilkan gambaran lebih
lengkap tentang Islam dan keragaman masyarakat Muslim Hong Kong.
Chinese University of Hong Kong (CUHK) agaknya merupakan universitas
paling bersemangat mengembangkan Kajian Islam. Sebelumnya CUHK telah
memiliki program Kajian Agama (religious studies), tetapi tidak mencakup
Kajian Islam. Namun, minat di lingkungan universitas ini terus meningkat,
sehingga pada 2009 dan awal 2013 menyelenggarakan dua konferensi besar
tentang peradaban Islam dan Muslim Cina dengan menghadirkan sejumlah
ahli dari Cina Daratan, Taiwan, Asia Tenggara, dan Hong Kong sendiri.
Karena itulah Prof Hsiung, Pin-Chen yang direktur Research Institute for the
Humanities (RIH) mengambil prakarsa mendirikan The Initiative in Islamic
Studies (ISI) pada akhir 2013 melalui kerja sama dengan Islamic Cultural
Association (ICA) Hong Kong. Perempuan asal Taiwan yang jebolan
Universitas Brown dan Harvard, AS, yakin sudah saatnya Islam dan kaum
Muslimin menjadi bagian integral dari kajian akademik-ilmiah di lingkungan
universitas.
Kajian Islam seperti apa yang ingin dikembangkan CUHK? Penulis Resonansi
ini yang diundang dalam Seminar ISI pada 8 Oktober 2014 menjelaskan
tentang distingsi Kajian Islam di tiga wilayah: dunia Arab, Barat, dan
Indonesia. Kajian Islam di dunia Arab dan Barat memiliki corak, pendekatan,
dan kecenderungan masing-masing yang sering mendapat kritik karena
yang pertama cenderung bersifat normatif, sedangkan yang kedua
cenderung „liberal‟.
Sedangkan kajian Islam Indonesia sedikitnya dalam empat dasawarsa
terakhir telah mengembangkan distingsinya sendiri; sebagiannya dengan
mengambil hal-hal terbaik dalam substansi, pendekatan, dan orientasi
Kajian Islam di dunia Arab dan Barat. Kajian Islam Indonesia selain tetap
mementingkan pendekatan normatif, misalnya, juga menekankan urgensi
pendekatan historis dan sosiologis secara analitis dan komparatif. Dengan
begitu, para pengkaji Islam tidak hanya melihat doktrin teologis dan
normatif Islam, tapi sekaligus melihat Islam sebagai realitas historis dan
sosiologis sehingga dapat memberi cakrawala dan pemahaman intelektual
lebih berimbang.
Pendekatan Kajian Islam model Indonesia bagi saya merupakan bentuk yang
pas bagi ISI CUHK. Dengan pendekatan Kajian Islam Indonesia, universitas-
universitas di Hong Kong dan/atau Cina secara keseluruhan dapat mengkaji
Islam „dari dalam‟ (from within), dan sekaligus „dari luar‟ (from without).
Dengan begitu bisa diperoleh pengetahuan dan pemahaman lebih
komprehensif tentang Islam dan masyarakat Muslim.
Presiden Baru, Harapan Baru
Wednesday, 22 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/21/ndsuyv-presiden-baru-harapan-baru
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan
wakil presiden baru Indonesia disambut dengan antusiasme pesta
kerakyatan yang meriah.
Setelah sekian lama jagat politik Indonesia mengalami lesu darah,
kemunculan pemimpin (relatif) autentik dalam pemilihan presiden kali ini
mengembalikan darah segar ke jantung politik. Kehadiran darah segar ini
lantas dipompakan ke seluruh tubuh kebangsaan oleh dorongan semangat
perubahan yang digerakkan oleh simpul-simpul relawan yang tersebar di
seluruh pelosok negeri.
Tanpa menunggu komando dan janji imbalan, simpul-simpul relawan ini
bergerak serempak, mengatasi keterbatasan logistik dan jaringan institusi
kepartaian. Sontak saja, Indonesia pun disapu gelombang partisipasi politik
rakyat yang masif, energetik, dan kreatif.
Kebangkitan musim semi kesukarelaan ini memberi dian pemandu untuk
keluar dari krisis kepercayaan dalam politik. Krisis ini muncul karena warisan
sisi-sisi gelap masa lalu yang tak sepenuhnya kita kenali. Untuk mengenali
sebab-sebabnya, kita harus berani menyusuri lorong gelap masa lalu untuk
menemukan visi dan formula perubahan yang tepat, bukan mengandalkan
resep-resep umum yang telah dikenal.
Bagi siapa saja yang bertekad menghadapinya, krisis yang diwariskan itu
bukanlah alasan untuk mencari kambing hitam, melainkan membuka
peluang bagi perubahan fundamental. Dengan sikap demikian, krisis
merupakan kritik alam tentang perlunya kerendahan hati bahwa
kemungkinan historis itu jauh lebih kaya dan beragam ketimbang konsepsi
intelektualitas manusia.
Oleh karena itu, betapa pun krisis bisa membawa tragedi kemanusiaan, kita
tidak boleh kehilangan harapan. Sikap yang diperlukan bukanlah
meremehkan masalah atau mengecilkan hati, melainkan optimisme realistis.
Warisan terbaik para pendiri bangsa ini adalah “politik harapan” (politics of
hope), bukan “politik ketakutan” (politics of fear). Republik ini berdiri di atas
tiang harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika kita
kehilangan harapan, kita kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia.
Pengalaman menjadi Indonesia menunjukkan bahwa spirit perjuangan
memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk menghadapi berbagai
rintangan karena adanya harapan. Kemarahan, ketakutan, dan kesedihan
memang tak tertahankan, tetapi sejauh masih ada harapan, semangat tetap
menyala.
Akan tetapi, politik harapan harus berjejak pada visi yang diperjuangkan
menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Di sinilah
titik genting politik Indonesia saat ini. Wacana dan perjuangan politik lebih
didorong oleh pertarungan kepentingan ketimbang pertarungan gagasan.
Melemahnya kekuatan visi membuat politik kehilangan responsibilitasnya.
Berbagai kebijakan dan pilihan politik yang dikembangkan sering kali tak
memenuhi empat prinsip utama suatu politik yang responsif: prinsip
kemasukakalan, efisiensi, keadilan, dan kebebasan.
Dengan keempat prinsip ini, politik yang responsif harus mempertimbangkan
rasionalitas publik tanpa kesemena-menaan mengambil kebijakan;
adaptabilitas kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan; senasib
sepenanggungan dalam keuntungan dan beban; serta persetujuan rakyat
terhadap pemerintah. Ketika arena politik lebih mewadahi konflik
kepentingan ketimbang konflik visi, watak politik menjadi narsistik,
mengecilkan harapan banyak orang.
Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang
mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta
keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi
kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan lewat
aktualisasi politik harapan.
Menurut Donna Zajonc, dalam The Politics of Hope, untuk merealisasikan
politik harapan suatu bangsa harus keluar dari tahap anarki, tradisionalisme,
apatisme menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap
pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan
kepentingan pribadi yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik.
Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu pemimpin mendominasi dan
memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang yang
dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya justru membuatnya
apatis.
Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari
pentingnya merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis dengan
cara memahami kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerja sama
menerobos batas-batas politik lama. Kekuasaan digunakan untuk
memotivasi dan memberi inspirasi yang memungkinkan orang lain
mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan
dalam politik dan aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan
kebajikan bersama.
Semua pihak harus menyadari bahwa politik, sebagaimana dikatakan
Hannah Arendt, adalah suatu “ruang penjelmaan” (space of appearance)
yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang.
Oleh karena itu, terang-gelapnya langit harapan di negeri ini sangat
ditentukan oleh warna politik kita.
Para pemimpin harus insaf bahwa ruang kebebasan yang memungkinkannya
berkuasa hanya dapat dipertahankan sejauh dipertautkan dengan tanggung
jawab dan penghormatan pada yang lain. Bermula dari keinsafan para
pemimpin di pusat teladan, semoga akan mengalir berkah ke akar rumput,
membawa bangsa keluar dari kelam krisis menuju terang harapan.
Solusi BBM dengan Mobil Listrik
Saturday, 18 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/17/ndlgrh-solusi-bbm-dengan-mobil-
listrik
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
Sebuah mobil sport sangat elegan bewarna kuning bertengger di salah satu
sudut ruang pameran Jakarta International Motor Show 2014. Tidak seperti
mobil lain yang dipamerkan di ruang terbuka hingga dapat dikagumi banyak
orang, mobil ini terkesan nyempil di sudut sempit ruang beratap terpal.
Pemandangan yang cukup membuat saya bertanya-tanya, bagaimana
mungkin mobil yang terlihat sangat mahal dan elegan, terparkir di tempat
yang tidak strategis?
Ternyata, mobil yang diberi nama Selo tersebut merupakan karya anak
bangsa. Lebih mengagumkan lagi, ia menggunakan bahan bakar listrik.
Selo adalah mobil dengan konsep sport car berbalut warna kuning yang
tampilannya dibuat oleh perajin mobil asal Yogyakarta, 'Kupu-Kupu Malam'.
Mobil rekaan para pionir mobil listrik Indonesia ini memiliki kecepatan
maksimum 200 km/jam, dengan kekuatan baterai yang mampu bertahan
hingga enam jam.
Melihat posisi di mana mobil mendapat tempat di JIMS 2014, saya bisa
menduga bahwa keberadaannya tidak mendapat dukungan sebagaimana
seharusnya, dan ternyata dugaan itu benar.
Tanpa alasan jelas, bahkan mobil yang prototipenya menghabiskan dana
miliaran rupiah ini masih sulit sekali mendapat izin jalan. Jika alasan
keamanan, saya yakin Selo jauh lebih aman dari bajaj buatan India yang
sudah melanglang buana di mana-mana.
Kecelakaan yang sempat terjadi pada prototipe pertama, dalam pendapat
saya, merupakan harga sebuah perkembangan teknologi. Kapal terbang
pertama juga jatuh sebelum jauh mengudara. Tidak diinginkan tentu, tetapi
merupakan bagian dari proses penyempurnaan.
Jika keraguan disebabkan alasan teknologi, meski asli Indonesia, sosok di
belakang pembuatan mobil listik ini, Ricky Elson, justru sudah dikenal
kiprahnya di Negeri Sakura. Pemuda asal Padang tersebut sedikitnya telah
menghasilkan sekitar 14 teori mengenai motor listrik dan telah pula
dipatenkan oleh Pemerintah Jepang.
Di perusahaan lamanya, Nidec Corporation, yang bergerak di bidang
elektronik dan memproduksi elemen motor presisi alias mikromotor, sekitar
80 persen produknya merupakan karya pemuda ini.
Apakah mobil listrik kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak karena
dikhawatirkan jika terwujud keberadaannya bakal mengancam industri
otomotif nasional? Tapi, alasan itu tidak masuk akal sebab jika mobil listrik
sudah sukses, otomotif dunia justru akan menyesuaikan diri karena saat ini
kelangkaan bahan bakar fosil sudah menjadi ancaman dunia.
Mobil listrik seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebab
memiliki banyak alasan logis yang dapat mengangkat harga diri bangsa
indonesia. Pertama, BBM adalah masalah paling utama yang menggerogoti
keuangan negara. Subsidi BBM menghabiskan 40 persen anggaran negara
dan juga tidak tepat sasaran. Harga BBM di Indonesia termasuk termurah,
lebih tepatnya nomor 13 termurah di dunia. Negara lain yang menjual lebih
murah adalah negara pengekspor minyak, sedangkan Indonesia kini adalah
pengimpor minyak. Bahkan, harga BBM kita lebih murah dari Venezuela dan
Uni Emirat Arab yang merupakan penghasil minyak utama di dunia.
Diperkirakan dalam kurun waktu 11 tahun jika tidak ada perubahan gaya
konsumsi BBM maka cadangan di Indonesia yang hanya 0,02 persen minyak
dunia akan habis. Kebutuhan minyak di Tanah Air saat ini sekitar 1,6 juta
liter per hari. Padahal, kilang minyak kita hanya menghasilkan 788 ribu barel
setiap hari. Tanpa perubahan berarti, pada tahun 2018 Indonesia bisa
menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia.
Kedua, mobil berbahan bakar listrik adalah energi yang terbarukan dengan
risiko terkecil terhadap kerusakan lingkungan. Ketika Barat mempromosikan
biodiesel, sekalipun kelihatannya ramah lingkungan, kenyataannya banyak
hutan alam yang ditebang untuk menanam tumbuhan untuk biodiesel
tersebut. Kebun sawit diperluas dan hutan alam dibabat. Dengan mobil
listrik kita tidak perlu lagi menebang hutan, cukup menambah sumber listrik
baru.
Ketiga, mobil listrik bebas polusi. Jakarta adalah salah satu kota dengan
polusi udara terbanyak, karenanya akan menjadi solusi yang
menguntungkan lingkungan hidup.
Keempat, mobil listrik bisa menempatkan Indonesia menjadi “pemain” baru
di dunia otomotif karena pada dasarnya kita sebenarnya punya potensi
mendahului bangsa asing.
Dengan begitu banyaknya keuntungan, tidakkah saatnya pemerintah ke
depan, Jokowi dan JK, menjadikan mobil listrik dalam daftar agenda penting
bangsa?
'Revolusi Payung' dan Muslimin Hong Kong
Thursday, 16 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/16/ndhp9f-revolusi-payung-dan-
muslimin-hong-kong
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
„Revolusi Payung‟ alias „Umbrella Revolution‟ —sebuah istilah populer
belakang ini-- mengacu pada gerakan prodemokrasi di Hong Kong.
Terutama didukung para mahasiswa dan aktivis demokrasi, demonstrasi
damai yang muncul sejak 22 September 2014 menyebut diri sebagai „Duduki
[Wilayah] Sentral dengan Cinta dan Perdamaian‟.
Para demonstran membawa payung, tidak hanya untuk menahan panas
matahari dan hujan, tapi juga sebagai tameng perlindungan dari semprotan
cabai halus dan gas air mata yang dilepas polisi Hong Kong dalam usaha
membubarkan mereka. Di luar insiden itu, tidak jelas sampai kapan
pendudukan beberapa ruas jalan di wilayah Sentral Hong Kong berlanjut.
„Revolusi Payung‟ bermula dari meningkatnya kekhawatiran warga Hong
Kong, khususnya kalangan muda, terhadap kian merosotnya kebebasan
yang membedakan kawasan bekas koloni Inggris ini dengan wilayah
Republik Rakyat Cina (PRC) lain. Padahal, ketika Inggris mengembalikan
Hong Kong kepada Beijing (1997), para warganya dijanjikan berada dalam
„satu negara, dua sistem‟ yang menjamin otonomi Hong Kong selama 50
tahun ke depan.
Para pemrotes juga menolak pemilihan kepala eksekutif (chief executive)
Hong Kong secara tidak langsung oleh semacam dewan pemilih yang
kebanyakan anggota adalah orang-orang pro-Beijing. Hasilnya, chief
executive Hong Kong selalu pro-Beijing daripada prowarga setempat. Karena
itu, mereka menuntut pemilihan langsung oleh warga —satu orang, satu
suara.
Apakah Beijing bakal memenuhi tuntutan para demonstran? Sejarawan
terkemuka Wang Gungwu dalam artikelnya „A Test of Will‟ dalam
HarianSouth China Morning Post (9 Oktober 2014) menyebut yang kini
terjadi di antara para demonstran pada satu pihak dengan polisi dan
Pemerintah Hong Kong pada pihak lain adalah „ujian kemauan‟ —siapa yang
lebih punya semangat bertahan. Sementara itu, pemerintah pusat di Beijing
memilih bersikap „menunggu‟ —mencoba menahan diri tidak terlibat
langsung, sementara berusaha memastikan tak ada campur tangan
kepentingan dan kekuatan luar.
Penulis Resonansi ini berkesempatan selama sepekan (6-12 Oktober 2014)
mengamati „Revolusi Payung‟ ketika kembali ke Hong Kong sebagai Visiting
Professor pada Research Institute of Humanities (RIH), Chinese University of
Hong Kong (CUHK). Bagi kalangan luar yang mengikuti pemberitaan televisi
dan media cetak, Hong Kong secara keseluruhan terlihat tengah bergolak.
Dalam kenyataan, pergolakan dan pendudukan terjadi hanya di kawasan
Sentral, Pulau Hong Kong. Kehidupan di wilayah lain, seperti Kowloon dan
New Territories tetap berlangsung seperti biasa.
Hal yang sama juga terlihat di lingkungan kaum Muslimin Hong Kong. Ketika
berkunjung ke Masjid Ammar di lingkungan Kowloon pada Jumat (10/10),
masjid dengan bangunan gedung berlantai delapan ini terlihat ramai oleh
jamaah. Jika jamaah laki-laki kebanyakan berwajah Pakistan, Bangladesh,
dan India, jamaah perempuan kebanyakan berparas Indonesia.
Muslimin asal Indonesia merupakan kelompok terbesar penganut Islam di
Hong Kong —sekitar 90 persen mereka Muslimat pekerja rumah tangga
(domestic workers) yang juga disebut BMI —buruh migran Indonesia.
Menurut data Pemerintah Hong Kong ada sekitar 140 ribu Muslim Indonesia
dan 30 ribu Muslim Cina yang sebagian besar berasal dari Cina daratan
(mainland). Sisanya dari anak benua India, Timur Tengah, dan Afrika.
Pembentukan Hong Kong sebagai diaspora Muslim bermula ketika kawasan
ini menjadi „koloni‟ Inggris sejak akhir 1880-an yang membawa pasukan dan
pegawai Muslim dari anak benua India. Komunitas Muslimin yang meski
masih kecil jumlahnya, berhasil membentuk Dewan Penyantun yang
kemudian membangun masjid di Shelley Street pada 1890 yang semula
disebut „Mohammedan Mosque‟. Nama masjid ini janggal —karena
sebenarnya tidak ada „Mohammedan mosque‟ atau „Mohammedan religion‟
sehingga pada 1905 diganti menjadi „Masjid Jami‟.
Sejak itu, beberapa masjid lagi didirikan sehingga berjumlah enam masjid
sampai sekarang. Keenam masjid itu adalah Masjid Kowloon, semula
dibangun pada 1896 dan direstorasi sebagai masjid terbesar dan terindah di
Hong Kong pada 1984; Masjid Ammar, pertama kali dibangun pada 1967
dan direhab total pada 1981; Masjid Stanley didirikan pada 1937; Masjid
Chai Wan dibangun pada 1963; dan terakhir Masjid Ibrahim yang dibangun
pada 2013.
Kaum Muslimat asal Indonesia mulai berdatangan ke diaspora Hong Kong
sejak 1980-an. Jumlah mereka terus meningkat pada 1990-an sehingga
menjadi komunitas Muslim terbesar di Hong Kong. Mbak Supartinah asal
Blitar yang sudah bekerja hampir selama 30 tahun di Hong Kong bercerita,
tidak banyak kaum lelaki Muslim Indonesia di Hong Kong —hanya sekitar
50-an orang karena jauh lebih sukar bagi mereka mendapat visa kerja.
Menurut Mbak Tinah yang berjilbab ini, kemudahan lebih banyak diberikan
kepada perempuan domestic workers.
Muslimat Indonesia kebanyakan bergabung dengan Masjid Ammar dan
Masjid Kowloon. Mereka tidak punya organisasi sendiri, tetapi bergabung
dengan Islamic Union yang bermarkas di Masjid Ammar. Mereka hampir
selalu mengafiliasikan diri dengan ormas di Indonesia seperti NU,
Muhammadiyah, misalnya. Para BMI ini menjadi pengirim remittancedalam
jumlah besar ke Indonesia dan sekaligus penopang filantropi Islam yang
tidak bisa diabaikan.
Restorasi GBHN
Wednesday, 15 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/14/ndfvrt-restorasi-gbhn
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Yang menjengkal dari kecenderungan sikap “ahli” dan pelaku politik
kontemporer di negeri ini adalah kegairahan untuk meninggalkan sistem
politik sendiri dengan mencangkokkan sistem dari negara adikuasa, namun
dengan cara tambal sulam.
Lewat empat kali amandemen Konstitusi, kedudukan kedaulatan (locus of
sovereignty) yang semula memusat di MPR dihapuskan. Para pelaku
amandemen mengira bahwa sistem pemerintahan yang meletakkan
kedaulatan di tiga tempat (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) seperti di
Amerika Serikat lebih demokratis ketimbang sistem pemerintahan yang
memusatkan kedaulatannya di satu “lembaga tertinggi” seperti sistem
Westminster di Inggris. Jarang disadari bahwa “kedaulatan” rakyat dalam
demokrasi tidak harus selalu dijalankan dalam bentuk pemisahan kekuasaan
(separation of power) seperti di Amerika Serikat. Yang terjadi di Inggris
malah suatu penggabungan kekuasaan (fusion of power) dengan
memusatkan kedaulatan rakyat di “parlemen”. Parlemen Inggris terdiri dari
3 unsur: Raja/Ratu di Parlemen sebagai unsur eksekutif, House of Commons
(yang dipilih langsung) dan House of Lords (yang ditunjuk) sebagai unsur
legislatif, dan juga mengandung unsur judicial karena law lords yang berada
di House of Lords merupakan “Appellate Committee” (peninjau keputusan
peraturan perundang-undangan).
Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar
1945 hampir menyerupai Inggris dalam hal memusatkan kedaulatan rakyat
di satu lembaga tertinggi, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Bedanya, fungsi dan kekuasaan MPR dalam sistem pemerintahan kita lebih
lemah ketimbang parlemen di Inggris. MPR sebagai parlemen di Indonesia
tidak mengandung unsur eksekutif dan judicial, dan fungsi utamanya hanya
merumuskan dua “norma hukum” tertinggi (UUD dan GBHN) yang dilakukan
oleh tiga unsur parlemen: DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.
Orde Reformasi tampaknya cenderung hendak meniru sistem Amerika
Serikat tetapi “salah arah”, karena tidak mengadopsinya secara konsisten.
Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) di Amerika Serikat hanya
dijalankan oleh lembaga perwakilan saja, yakni Kongres, yang merupakan
gabungan antara house of representatives (DPR) dan senate (DPD).
Resminya, Presiden AS dilarang untuk menyampaikan rancangan undang-
undang ke Kongres. Adapun kekuasaan membuat undang-undang dalam
sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Konstitusi tidak hanya
dijalankan oleh lembaga perwakilan. Meskipun pasal 20 ayat 1 menyatakan:
“DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang”, tetapi ketentuan ini
dimentahkan oleh ayat 2: “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Artinya, kita tidak
konsisten menjalankan konsep pemisahan kekuasaan, karena Presiden
masih ikut dalam pembuatan undang-undang.
Setelah MPR dijatuhkan posisinya dari lembaga tertinggi, kewenangannya
dalam menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga ditiadakan.
Sebagai gantinya, muncul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang- Undang. RPJPN ini kemudian
diturunkan ke dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) untuk
periode lima tahunan, dengan memberi kesempatan kepada Presiden untuk
menentukan platform politik pembangunannya tersendiri, sesuai dengan
janji kampanye.
Masalahnya, karena RPJP ini ditetapkan oleh undang-undang, maka Presiden
ikut serta dalam merumuskan ketentuannya. Setelah itu, karena Presiden
juga diberikan kewenangan untuk menetapkan platform pembangunan,
maka Presiden juga yang menjalankan undang-undang itu dan menetapkan
anggarannya. Dan akhirnya, karena tidak ada mekanisme
pertanggungjawaban kepada MPR, maka Presiden juga yang mengawasi
pelaksanannya. Alhasil, jika Presidennya tidak amanah, mudah sekali
kebijakan pembangunan di negeri ini jatuh ke tangan kepentingan
perseorangan, yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Hal ini amat berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di
Amerika Serikat. Di sana, meskipun Presiden diberikan wewenang untuk
menetapkan platform kebijakannya, namun fungsi Kongres dalam
menentukan anggaran lebih kuat. Sesuai dengan sistem pemisahan
kekuasaan, baik Senat dan DPR di AS harus sama-sama menyetujui
anggaran, kemudian ditandatangani Presiden Amerika Serikat. Jika Presiden
tidak setuju atas rancangan anggaran yang ditetapkan Kongres, Presiden
bisa memvetonya, dan rancangan anggarannya dikembalikan ke Kongres. Di
Kongres, veto tadi dapat dibatalkan dengan dua per tiga suara menolak.
Oleh karena itu, kerap terjadi dalam sejarah AS, perselisihan dalam Kongres
atau veto Kongres atas veto Presiden berdampak pada penutupan
pemerintahan (shut down), seperti terjadi belum lama ini.
Selain persoalan teknis-instrumental, ada persoalan prinsipil. Dalam
konsepsi negara kekeluargaan, haluan negara sebagai norma dasar itu
mestinya dirumuskan oleh pelbagai representasi kekuatan politik dalam
lembaga tertinggi negara (MPR). Ekses negatif dari kewenangan MPR
sebagai lembaga tertinggi negara di masa lalu sebenarnya bisa saja
dihilangkan. Artinya, Presiden tidak perlu lagi dipilih oleh MPR; dan MPR juga
tidak bisa langsung menjatuhkan Presiden tanpa melalui mekanisme
impeachment yang memerlukan pengajuan DPR dan keputusan Mahkamah
Konstitusi. Namun, dalam ketentuan prosedur impeachment pada UUD
pasca amandemen pun sebenarnya terkandung pengakuan terselubung,
yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Karena MPR-lah yang
diberikan wewenang sebagai pemutus terakhir bisa atau tidaknya Presiden
dimakjulkan. Seturut dengan itu, mestinya tidak perlu ada keraguan untuk
mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN dalam versi
yang lebih disempurnakan dari produk GBHN di masa lampau.
Danau Dendam tak Sudah
Selasa, 14 Oktober 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/13/nde12d-danau-dendam-tak-sudah
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Saya sudah lama penasaran untuk suatu saat bisa mengunjungi DDTS
(Danau Dendam Tak Sudah), sekitar enam km dari Kota Bengkulu, dikitari
oleh empat kecamatan: Teluk Segara, Seleber, Talang Empat, dan Bengkulu
Tengah. Bagi saya nama ini demikian puitis, jika bukan romantis, sekalipun
menurut legenda rakyat memuat cerita tragis-dramatis. Diantar oleh
pimpinan wilayah dan pimpinan UMB (Universitas Muhammadiyah
Bengkulu), pada 8 Okt. siang kerinduan saya untuk menyaksikan dari dekat
DDTS itu menjadi kenyataan sudah. Angan-angan melayang jauh
menyaksikan ombak danau yang damai bersahabat. Cantik nian danau ini,
tetapi namanya tetap saja mengundang tanda tanya yang sarat misteri.
Tiba-tiba nalar politik saya muncul saat menyebut DDTS, melayang ke
Sidang DPR, pada 1-2 Okt. 2014, yang brutal dan main sapu bersih itu.
Tidak satu pun yang tersisa kursi pimpinan DPR untuk parpol yang
berseberangan, sesuatu yang tak elok diteruskan oleh sesama anak bangsa.
Maka di sini berlaku pula dendam tak sudah sebagai ekor dari kekalahan
dalam pilpres pada 9 Juli yang lalu. Berbeda dengan suasana di DPR, proses
pemilihan pimpinan MPR, sekalipun alot selama berjam-jam, terasa lebih
beradab. Bahwa siapa pemenangnya tidak lagi dipersoalkan, karena
perdebatan relatif telah berlangsung dalam iklim demokrasi terbuka tanpa
diselimuti dendam yang menggebu, padahal sebagian besar pemainnya
orang yang sama juga.
Sebelum Sidang MPR, saya kirim SMS kepada pimpinan DPD agar mereka
tampil sebagai negarawan yang sedang inflasi di DPR. SMS saya ditanggapi
positif, sekalipun DPD sendiri tidak kompak mendukung calonnya untuk
diusung menjadi Ketua MPR. Dengan terpilihnya Zulkifli Hasan dari PAN
sebagai Ketua MPR yang baru, suasana politik sedikit berubah ke arah yang
lebih tenang, lebih sejuk, berkat pernyataan singkatnya yang bernada damai
setelah terpilih. Kepada ketua baru ini SMS saya sore 8 Okt. berbunyi:
“Selamat memimpin MPR, semoga diberkati Allah, demi keutuhan bangsa
dan negara.” SMS ini satu menit kemudian dibalas dan diamini oleh yang
bersangkutan sambil mengucapkan terima kasih. Tentu saja ke depan
semua kita tidak boleh membiarkan bangsa dan negara ini terkoyak oleh
perasaan dendam berkepanjangan. Kemenangan dan kekalahan dalam
pertandingan adalah lumrah belaka. Yang tidak lumrah dan tidak sehat
adalah memelihara sikap dendam yang menguras energi secara sia-sia.
Perkataan dendam tidak selalu berkonotasi buruk, tergantung kepada kata
pendampingnya. Ungkapan rindu-dendam adalah suasana batin mereka
yang sedang dimabuk cinta, tetapi dendam-kesumat atau balas dendam bila
dikaitkan dengan perpolitikan Indonesia tercermin dalam Sidang DPR di atas
jelas semakin merusak tatanan demokrasi yang memang sudah rusak.
Taruhannya adalah 250 juta rakyat Indonesia akan menderita dan
tersandera oleh kelakuan elite yang suka balas dendam itu. Jalan ke luarnya
adalah kesediaan membebaskan diri dari virus dendam, demi keutuhan
bangsa dan negara yang sedang oleng ini. Dalam sistem politik demokrasi di
mana pun di muka bumi, kekuatan oposisi sangat diperlukan agar
pemerintah tidak menyimpang dari acuan konstitusi dan amanat rakyat.
Tetapi oposisi yang ingin terus melibas lawan politiknya tanpa nalar bisa
meruntuhkan sistem demokrasi yang dengan susah payah telah dibangun.
Kembali ke DDTS. Setidak-tidaknya ada dua versi tentang asal-usul nama
danau itu. Legenda mengatakan bahwa jauh di masa silam, entah kapan,
ada dua sejoli yang saling jatuh cinta, tetapi terbentur karena dihalangi oleh
orang tua pihak perempuan yang ingin punya menantu peria lain. Dua sejoli
yang telah bersatu hati itu menempuh jalan singkat: bunuh diri dengan
terjun ke dalam danau untuk tidak muncul lagi. Rindu-dendam yang tidak
kesampaian itu diabadikan menjadi DDTS karena di sanalah dua sejoli yang
malang itu berkubur dengan kedalaman sekitar 15 meter.
Versi lain mengatakan bahwa pemerintah kolonial pernah punya rencana
membangun dam untuk menata aliran air danau itu. Sampai usai
penjajahan, dam itu tidak pernah menjadi kenyataan. Entah bagaimana
ceritanya sebelum kata „dam‟ diberi kata „den‟, menjadi dendam. Karena
dam itu tidak pernah disudahkan, maka muncullah ungkapan puitis DDTS.
Bagi saya yang kedua ini sama sulitnya diterima seperti juga asal-usul nama
yang pertama. Lalu?: antahlah yuang, kata orang Minang. Tetapi bagaimana
pun, bagi saya DDST tetap saja menyiratkan nuansa puisi, sedangkan sikap
dendam yang dipertontonkan di Senayan mewakili sosok politisi yang
sedang haus kekuasaan dengan cara menyapu bersih lawan politiknya dari
posisi pimpinan.
Nobel Perdamaian Buat Sweet Seventeen
Senin, 13 Oktober 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/13/ndbrdw-nobel-perdamaian-buat-
sweet-seventeen
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Malala namanya. Tepatnya Malala Yousafzai. Usianya baru 17 tahun.Sweet
seventeen, istilahnya. Namun, meskipun masih belia, remaja putri dari
Pakistan ini oleh Komite Nobel -- dalam pengumuman yang disampaikan di
Oslo, Norwegia, pada Jumat (10/10) lalu -- dinyatakan berhak menerima
penghargaan bergengsi Nobel Perdamaian Tahun 2014.
Lalu apa makna Malala bagi dunia sehingga dia disejajarkan dengan nama-
nama besar seperti Martin Luther King Jr, Anwar Sadat, Manachem Begin,
Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, Yasir Arafat, dan Barack
Obama? Nama-nama yang tersebut tadi merupakan di antara tokoh-tokoh
dunia yang pernah menerima Penghargaan Nobel Perdamaian.
Malala memang tidak sendirian menerima Nobel Perdamaian Tahun 2014. Ia
berbagi dengan Kailash Satyarthi. Kedua orang ini mengalahkan 278 calon
lainnya. Malala dan Satyarthi akan menerima hadiah sekitar 1,1 juta dolar
AS.
Satyarthi adalah warga India, 60 tahun. Ia dinilai layak menerima Nobel
Perdamaian karena perjuangannya membela hak-hak anak di negaranya.
Sejak 1990-an ia aktif menentang industri India yang mengekploitasi buruh
anak. Pada 1998 ia memulai sebuah pawai global tahunan untuk menentang
praktek pekerja anak. Komite memuji Satyarthi telah „memelihara tradisi
Gandhi‟ dalam aksi-aksi damai memperjuangkan hak asasi anak-anak.
Bagaimana dengan Malala? Pada 2009, ketika usianya baru 11 tahun, ia
sudah dikenal dunia lewat buku hariannya yang dimuat BBC bahasa Urdu.
Dengan nama samaran Gul Makai, Malala menyerukan tentang pentingnya
anak-anak perempuan di negerinya mendapatkan pendidikan seperti halnya
anak laki-laki. Pada usia 15 tahun, tepatnya 9 Oktober 2012, ia dan teman-
temannya diberondong tembakan saat berada di bus dalam perjalanan
pulang dari sekolah. Belakangan diketahui pelakunya adalah kelompok
Taliban.
Malala tertembak di kepalanya. Untungnya nyawanya masih selamat.
Beberapa waktu kemudian ia diterbangkan ke sebuah rumah sakit di London
untuk menjalani perawatan. Lantas apa hubungan antara buku harian Malala
dengan peristiwa penembakan? Atau lebih tepatnya dengan Taliban?
Dalam buku hariannya, Malala menulis tentang kehidupan di Lembah Swat,
saat wilayah indah yang dijuluki „Swissnya Pakistan‟ itu dikendalikan rezim
Taliban sejak 2007. Lembah Swat berada di barat daya Pakistan, berbatasan
dengan Afghanistan. Taliban berkuasa di daerah itu selama dua tahun
hingga didesak mundur militer Pakistan pada 2009. Selama berkuasa, rezim
Taliban menutup semua sekolah untuk anak perempuan, termasuk sekolah
yang dimiliki oleh ayah Malala, Ziauddin Yousafzai.
Ziauddin adalah seorang guru. Ia mendorong anak perempuannya untuk
bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Namun, keinginan sang bapak dan
anak yang bercita-cita menjadi dokter tampaknya harus tertunda lantaran
Taliban melarang anak gadis bersekolah.
Ketika Taliban keluar dari Swat, Malala pun kembali bersekolah. Tapi,
„dendam‟ Taliban kepada remaja perempuan yang masih berusia 15 tahun
dan terus menyerukan anak-anak perempuan untuk bersekolah itu
tampaknya belum hilang. Puncaknya terjadi pada 9 Oktober 2012 ketika
segerombolan orang-orang Taliban menembaki bus yang ditumpangi Malala
dan teman-temannya dalam perjalanan pulang sekolah.
Di sinilah makna penting kehadiran Malala. Ia berani melawan sebuah rezim
yang didominasi kaum laki-laki. Sebuah rezim yang meletakkan kaum
perempuan hanya sebagai „objek‟ atau „pelengkap penderita‟. Malala
memberontak. Ia melawan. Melawan sebuah rezim seperti Taliban yang
pernah berkuasa di Afghanistan antara 1996 hingga 2001.
Kehidupan di Afghanistan era Taliban berkuasa benar-benar didominasi
kaum laki-laki. Kaum perempuan hanya berkegiatan di sekitar rumah.
Sekolah dilarang. Ke pasar atau belanja ditabukan kecuali disertai
muhrimnya. Apalagi terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik.
Pendek kata, peran perempuan hanyalah di rumah dan di rumah: menjadi
istri, melayani suami, melahirkan, merawat anak, dan seterusnya.
Afghanistan era Taliban yang dideklarasikan dengan nama The Islamic
Emirate of Afghanistan jelas merupakan promosi buruk sebagai negara
Islam. Selain diwarnai dengan kekerasan dan konflik internal, Afghanistan
masa Taliban juga tertinggal dalam berbagai bidang, baik ekonomi,
pendidikan, maupun sosial budaya.
Namun, di negeri Malala sendiri, Pakistan, meskipun menolak „paham‟
Taliban, negeri itu sebenarnya menyimpan banyak masalah. Antara sang
kaya dan si miskin terdapat perbedaan mencolok. Panggung politik
didominasi keluarga-keluarga feodal, kaya, dan berpengaruh, semacam
Bhutto, Chaudhry, Zia-ul-Haa, Le-gha ri, Sajjad, Musharraf, Syarif, Gillani,
dan Zardari. Mereka kalau bukan keluarga pengusaha, ya tuan tanah atau
jenderal berpengaruh.
Sedangkan panggung kehidupan sosial kemasyarakatan lebih banyak
diperankan para ulama lokal dengan basis sekolah agama, seperti pesantren
tempat belajar kebanyakan orang miskin. Di sinilah gesekan atau bahkan
konflik internal sering terjadi antara politikus dan ulama. Persoalannya
bukan hanya murni dalih agama atau kepentingan nasional, tapi juga
masalah pribadi atau kelompok. Ini belum termasuk persaingan para
politikus yang sangat keras dalam memperebutkan kekuasaan. Juga,
perebutan pengaruh antarinternal tokoh agama hanya karena beda paham,
aliran, atau pendapat.
Itulah sebabnya, suksesi kekuasaan di Pakistan beberapa kali berjalan tidak
normal. Kudeta kekuasaan sering kali terjadi, baik dengan alasan tuduhan
korupsi maupun penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Bahkan sejumlah
politikus mati terbunuh atau dibunuh. Benazir Bhutto -- pernah menjadi PM
dua kali -- mati terbunuh saat kampanye. Ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto --
yang juga pernah menjadi presiden dan PM -- mati dihukum gantung oleh
Presiden Muhammad Zia-ul-Hak. Yang terakhir ini, juga tewas dalam
ledakan pesawat udara.
Sedangkan nasib kaum perempuan pun setali tiga uang. Hanya anak-anak
orang kaya dan politikus yang bisa mengenyam pendidikan yang baik.
Benazir Bhutto misalnya, lulusan Oxford dan Harvard. Atau, Hina Rabbani
Khar yang merupakan perempuan termuda yang pernah menjabat menteri
luar negeri Pakistan. Saat dilantik pada Juli 2011, usianya baru 34 tahun.
Hina berasal dari keluarga kelas atas Pakistan. Ayahnya, Ghulam Rabbani
Khar, adalah politikus dan tuan tanah. Hina lulusan Universitas
Massachusetts, AS, bidang manajemen dan bisnis.
Sementara itu, bagi perempuan Pakistan pada umumnya, terutama yang
tinggal di desa-desa, tentu tidak bisa bernasib sebaik Bhutto dan Khar.
Nasib kaum perempuan kebanyakan, jangankan menjadi politikus,
memperoleh pendidikan yang baik pun masih merupakan barang langka.
Di sinilah relevansi penghargaan Nobel Perdamaian buat Malala. Gadis belia
17 tahun ini telah membetot perhatian dunia bahwa masih banyak kaum
perempuan yang bernasib malang. Bukan hanya belum berkesempatan
mengenyam pendidikan yang baik, tapi juga kerap menjadi objek berbagai
kekerasan
Ebola, Virus yang tak Memandang Kewarganegaraan
Sunday, 12 October 2014, 13:32 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/12/ndbjhp-ebola-virus-yang-tak-
memandang-kewarganegaraan
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Asma Nadia
"Satu orang penderita ebola meninggal!" kalimat Scott Sugawara, salah satu
rekan fotografer yang saat ini sama-sama sedang berburu foto di Amerika.
Sekalipun belum sampai tahap mengkhawatirkan, berita kematian Thomas
Eric Duncan, korban warga negara Liberia ini, diumumkan langsung oleh
Menteri Luar Negeri Amerika. Salah satu kritik media terhadap Rumah Sakit
Texas Health Presbyterian Hospital Dallas adalah bagaimana RS tersebut
mengirim sang pasien pulang, padahal ia baru saja datang dari negeri yang
merupakan salah satu daerah terjangkit ebola terparah. Tiga hari kemudian
sang pasien kembali dan tak lama kemudian meninggal.
Seandainya saja sejak hari pertama memeriksakan diri ia langsung diawasi
sebagai potensial pasien Ebola, tentu hal ini tidak menjadi kekhawatiran
nasional.Diketahui 114 orang di Amerika bertemu dengan sang korban dan 9
di antaranya berada dalam risiko, sekalipun tidak ada gejala terjangkiti
ebola. Duncan sendiri tertular Ebola ketika menolong seorang ibu hamil di
Liberia, dan kemudian sang ibu meninggal akibat Ebola. Konon penyakit ini
menular melalui cairan tubuh yang terjangkiti virus.
Saat ini Amerika dan negara maju lain sedang berpikir keras agar penyakit
tersebut tidak menyebar di wilayah mereka.Apa hikmah yang terkandung
dari peristiwa ini?
Berbicara tentang Ebola, maka kita berbicara tentang virus. Hal-hal yang
kebanyakan orang lupa adalah: virus tidak peduli kebangsaan, hierarki,
rasis, miskin atau kaya, budak atau raja. Virus tidak peduli jika seseorang
berkulit putih, hitam atau merah. Virus hanya bertahan hidup dan
berkembang biak.
Ketika kita memerangi virus dengan begitu banyak keterbatasan dan isu-isu
seperti wilayah, kebangsaan, keuangan, budaya, keuangan dan isu-isu
etnis, maka selamanya tidak akan pernah bisa mengalahkannya.
Sayangnya, itu adalah realitas yang menjangkiti pikiran sebagian besar dari
kita hari ini.
Di Afrika sejak bulan Maret sampai awal Oktober 2014, 7.400 orang
terjangkiti dan sekitar 3.400 orang meninggal karena virus Ebola. Sierra
Leone Liberia, Guinea dan Nigeria adalah negara terparah yang terserang
penyakit ini.
Realitas paling tragis dalam situasi ini adalah perbandingan jumlah dokter
dan penduduk di negara-negara tersebut sangat rendah. Satu dokter di
negara-negara terjangkit ebola harus menangani seratus ribu orang. Dengan
perbandingan 1:100.000 negara-negara ini telanjang menghadapi serangan
virus.
Sierra Leone misalnya, mengambil langkah yang sangat kontroversial untuk
mengurangi penyebarannya. Pemerintah melarang enam juta penduduknya
keluar dari rumah mereka selama tiga hari. Hanya pejabat kesehatan yang
diizinkan melakukan perjalanan. Beberapa warganya kelaparan di rumah
karena tidak memiliki cukup makanan, sementara mereka tidak bisa keluar.
Yang menarik bagi saya adalah bagaimana dunia membiarkan negara-
negara tinggi resiko hanya memiliki satu dokter untuk seratus ribu orang,
tanpa melakukan bantuan berarti untuk memperbanyak jumlah dokter di
wilayah tersebut.
Idealnya satu dokter berbanding 500 orang. Indonesia adalah yang
terburuk di ASEAN dengan perbandingan 1 dokter untuk 3.400 orang,
sementara Amerika Serikat memiliki satu dokter untuk 400 warganya.
Dunia harus ingat bahwa kurangnya jumlah dokter di Afrika, tidak hanya
masalah Afrika. Ingat bahwa virus tidak memiliki kewarganegaraan, setelah
mereka tumbuh dan berkembang biak di Afrika bisa saja menyebar dan
tumbuh di seluruh dunia.
idealnya sejak lama, tanpa menunggu apapun wabah virus, dunia harus
menyediakan lebih banyak dokter di daerah Afrika atau rentan. Jika kita
melakukan itu, kita mungkin akan lebih siap mengantisipasi berbagai situasi.
Hari ini kita memiliki AIDS di seluruh dunia yang dimulai dari Afrika, dan
sekarang Ebola mulai dari Afrika lagi. Dan jika kita tidak memulai tindakan
antisipasi dari sekarang, siapa yang mampu menjamin tidak akan ada lagi
virus dimulai dari Afrika?
Saatnya bertindak, lupakan masalah kebangsaan, etnis dan keterbatasan
lain ketika kita berbicara tentang kesehatan, sebelum terlambat. Untuk
melawan virus, kita harus berada dalam satu visi yakni hanya berbicara
tentang kemanusiaan.Pemerintah semoga tak menunggu virus ini masuk ke
Indonesia baru panik. Sedini mungkin, sejak sekarang seharusnya sudah
ada langkah antisipasi yang bisa diandalkan. Sudahkah?
Winners Take All
Thursday, 09 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/08/nd4tm7-winners-take-all
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra
Pak Made. Inilah sopir yang mengantar saya bolak balik dari Hotel Amandari
ke venues Ubud Writers and Readers pada awal Oktober 2014 lalu.
Mengenali saya yang katanya „sering dia lihat di TV‟, pak Made secara serta
merta mengungkapkan keluhan dan sekaligus kegusaran dan kemarahannya
mengikuti perkembangan politik Indonesia pasca-Pilpres 9 Juli 2014.
Pak Made seperti banyak masyarakat lapisan bawah Indonesia yang sering
bertemu saya dalam perjalanan ke berbagai pelosok tidak bisa dipandang
remeh (underestimate); mereka sama sekali tidak buta dan tidak tuli,
sebaliknya sangat mawas politik. Mereka menonton televisi dan membaca
koran; mereka menyimak perkembangan politik tanahair baik yang
menyenangkan maupun tidak. Ketika mereka berkeluh kesah, saya sering
tergagap tidak bisa menjelaskan baik dan masuk akal apa yang tengah
terjadi dalam kancah politik Indonesia sekarang.
Pak Made sangat cemas dengan masa depan pemerintahan Jokowi-JK.
Setelah memenangkan Pilpres dengan disahkan KPU dan MK, kubu Jokowi-
JK dan Koalisi PDI-P mengalami kekalahan demi kekalahan berhadapan
dengan kubu koalisi Prabowo sejak dari penetapan UU MD3 yang
menentukan pemilihan pimpinan DPR RI melalui paket lima fraksi dan
penetapan UU Pilkada yang merampas hak rakyat memilih gubernur, bupati
dan wali kota secara langsung. Hasil pemilihan pimpinan DPR RI
berdasarkan UU MD3 sudah jelas; koalisi Prabowo menyapu bersih pimpinan
DPR RI—mereka mewujudkan prinsip winners take all, para pemenang
mengambil semuanya.
Gejala winners take all sebenarnya tidak aneh karena sejumlah negara
demokrasi, seperti Amerika Serikat misalnya, juga pada praktiknya juga
sering menerapkan hal seperti itu. Meski demikian, pemenang yang
menyapu bersih semua posisi di parlemen sering menimbulkan kemacetan
pemerintahan („government shut down‟) seperti hampir selalu pernah
dialami pemerintah Amerika sejak di bawah Presiden Ford, Carter, Reagan,
Clinton sampai Bush dan Obama. „Penutupan Pemerintahan‟ terjadi ketika
Kongres apakah ketika didominasi Partai Republik atau dikuasai Partai
Demokrat menolak menyetujui APBN atau program tertentu yang
memerlukan dana besar yang akhirnya mengakibatkan pelayanan
pemerintah harus ditutup.
Apakah pemerintah Jokowi-JK bakal mengalami shut-down sepanjang
pemerintahannya? Sejauh menyangkut APBN, jika DPR RI yang dikuasai
kubu Prabowo menolak pengesahan anggaran 2016 misalnya, pemerintahan
Jokowi-JK masih dapat menjalankan APBN tahun sebelumnya, 2015 yang
sudah disetujui DPR RI periode 2009-2014. Meski ada „pintu darurat‟
(emergency exit) semacam ini, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi-
JK satu waktu kelak mengalami hambatan DPR RI yang sulit diatasi—yang
pada gilirannya membuat sangat sukar bagi terlaksananya program
pembangunan secara baik.
Winners take all yang merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia
jelas adalah semacam show-down—unjuk gigi koalisi Prabowo setelah
menelan kekalahan pahit dalam Pilpres yang belum juga bisa mereka terima
secara legowo. Bisa terasa dan terlihat, gerakan sapu bersih itu
mengandung ill-intention, niat tidak baik untuk membuat pemerintahan
Jokowi-JK tidak bisa atau sulit bergerak.
Tetapi perkembangan winners take all tampak lebih daripada sekadar untuk
„mengganggu‟ pemerintah Jokowi-JK. Sejauh ini, manuver kubu Prabowo
yang kelihatan terus mendapat momentum, telah mengarahkan
pertumbuhan demokrasi dengan dampak jangka panjang yang tidak lain
terus memundurkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Karena itu, setiap
dan seluruh warga yang peduli dengan masa depan demokrasi negeri ini
mesti mencermati agar dapat melakukan respons yang tepat pula.
Hal ini terlihat jelas dalam penetapan UU Pilkada yang merampas hak
demokratis warga untuk secara langsung memilih kepala daerah (gubernur,
bupati, dan wali kota). Sebaliknya melalui UU Pilkada yang baru ini
pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD seperti berlaku pada
masa Orde Baru.
Jika judicial review dari berbagai pihak ke MK untuk pembatalan UU Pilkada
tersebut atau Perppu yang diajukan Presiden SBY di hari-hari akhir masa
kekuasaannya ditolak DPR RI nanti, hampir bisa dipastikan jabatan kepala
daerah merupakan ajang bagi-bagi kekuasaan (horse trading) di antara
partai-partai pendukung Koalisi Prabowo. Seperti pernah dinyatakan Wakil
Ketua KPK Bambang Widjojanto, jika money politics pada Pilkada langsung
lebih merupakan petty corruption—korupsi kelas teri, maka Pilkada lewat
DPRD bakal menimbulkan eksplosi money politics dalam skala yang sulit
dibayangkan.
Dampak jangka panjang manuver kubu Probawo lainnya sudah banyak
dibicarakan publik, di antaranya termasuk upaya melalui MPR untuk tidak
melantik Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih; atau jika
tetap dilantik kemudian dalam perjalanan pemerintahannya berupaya
memakzulkan keduanya; dan juga mengembalikan pemilihan presiden dan
wakil presiden kepada MPR RI seperti terjadi pada masa Orde Lama
khususnya.
Dengan perkembangan dan gejala politik seperti ini Pak Made dan rakyat
tinggal gigit jari; mereka seolah powerless—tidak berdaya apa-apa selain
mengurut dada. Atau bangkit kembali sebagai people power seperti pernah
terjadi pada bulan-bulan awal 1998. Jika hal terakhir ini terjadi, bukan tidak
mungkin biaya yang harus dibayar negara-bangsa Indonesia menjadi sangat
mahal.
Basis Karakter Kemajuan
Rabu, 17 September 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/09/16/nbzykv-basis-karakter-kemajuan
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Presiden Indonesia pertama, Soekarno, mengisahkan pengalaman yang
menggugah ketika beliau diwisuda di Technische Hoogeschool (Sekarang
Institut Teknologi Bandung). Ketika Rektor menyerahkankan ijazah insinyur
kepada Bung Karno, secara mengejutkan ia berkata, “Ir Soekarno, ijazah ini
suatu saat dapat robek dan hancur menjadi abu. Dia tidak abadi. Ingatlah,
bahwa satu-satunya hal yang abadi adalah karakter dari seseorang.” Atas
ucapan tersebut Bung Karno mengatakan, “Kenangan terhadap karakter itu
akan tetap hidup, sekalipun dia mati. Aku tak pernah melupakan kata-kata
ini” (Adam, 2011: 81).
Karakter adalah lukisan sang jiwa; ia adalah cetakan dasar kepribadian
seseorang/sekelompok orang, yang terkait dengan kualitas-kualitas moral,
ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, sebagai hasil dari suatu
proses pembudayaan dan pelaziman (habitus). Sedemikian pentingnya nilai
karakter bagi eksitensi seseorang/sekelompok orang, sehingga dalam
peribahasa Inggris dikatakan, “When wealth is lost, nothing is lost; when
healt is lost, something is lost; when character is lost, everything is lost.”
Apapun yang dimiliki seseorang, kepintaran, keturunan, keelokan,
kekuasaan menjadi tak bernilai jika seseorang tak bisa lagi dipercaya dan
tak memiliki keteguhan sebagai ekspresi dari keburukan karakter.
Karakter bukan saja menentukan eksistensi dan kemajuan seseorang,
melaikan juga eksistensi dan kemajuan sekelompok orang, seperti sebuah
bangsa. Ibarat individu, pada hakekatnya setiap bangsa memiliki
karakternya tersendiri yang tumbuh dari pengalaman bersama. Pengertian
“bangsa” (nation) yang terkenal dari Otto Bauer, menyatakan bahwa,
“Bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak, yang
persatuan karakter atau watak ini tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan
pengalaman.”
Perhatian terhadap variabel budaya terutama karakter, sebagai bagian yang
menentukan bagi perkembangan ekonomi dan politik suatu
masyarakat/bangsa pernah mengalami musim seminya pada tahun 1940-an
dan 1950-an. Para pengkaji budaya pada periode ini, dengan sederet nama
besar seperti Margareth Mead, Ruth Benedict, David McClelland, Gabriel
Almond, Sidney Verba, Lucian Pye dan Seymour Martin Lipset, memunculkan
prasyarat nilai dan etos yang diperlukan untuk mengejar kemajuan bagi
negara-negara yang terpuruk pascaperang Dunia kedua.
Namun, seiring dengan gemuruh laju developmentalisme yang menekankan
pembangunan material, pengkajian tentang budaya mengalami musim
kemarau pada tahun 1960-an dan 1970-an.
Kegagalan pembangunan di sejumlah negara, setelah melewati pelbagai
perubahan ekonomi dan politik, menghidupkan kembali minat dalam studi
budaya sejak tahun 1980-an. Pada 1985, Lawrence Horrison dari Harvard
Center for International Affairs menerbitkan buku, Underdevelopment Is a
State of Mind: The Latin American Case, yang menunjukkan bahwa di
kebanyakan negara Amerika Latin, budaya merupakan hambatan utama
untuk berkembang.
Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan ekonomi tampak dalam
kasus negara-negara multibudaya. Sekalipun semua kelompok etnis
dihadapkan pada hambatan sosial-politik dan krisis ekononomi yang sama,
namun sebagian kelompok lebih berhasil dibanding kelompok lainnya.
Ambillah contoh keberhasilan minoritas etnis Tionghoa di Asia Tenggara,
minoritas Jepang di Brazil, Basque di Spanyol, serta Yahudi ke mana pun
mereka bermigrasi.
Pentingnya variabel budaya dalam perkembangan politik ditunjukkan antara
lain oleh riset yang dilakukan oleh Robert Putnam (1993) dan Ronald
Inglehart (2000). Menurut Putnam, budaya adalah akar dari perbedaan-
perbedaan yang besar antara Italia utara yang bercorak demokratis dan
Italia Selatan yang bercorak otoritarian. Kesimpulan kedua ilmuwan tersebut
mewarisi pemikiran rintisan dari Alexis de Tocqueville (1835), yang
menyimpulkan bahwa apa yang membuat sistem politik Amerika berhasil
adalah kecocokan budayanya dengan demokrasi.
Tentang pentingnya karakter bagi suatu bangsa, Bung Karno sering
mengajukan pertanyaan yang ia pinjam sejarawan Inggris, H.G. Wells, “Apa
yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa?” Lantas ia jawab sendiri,
bahwa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa bukanlah seberapa
luas wilayahnya dan sebera banyak penduduknya, melainkan tergantung
pada kekuatan tekad, sebagai pancaran karakternya.
Dalam Amanat Proklamasi, 17 agustus 1956, Bung Karno mengingatkan
pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar
kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. ”Bangsa Indonesia
harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus mempunyai
levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi-hidup
dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang
dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai
levensdiepte samasekali. Ia adalah bangsa penggemar emas-sepuhan, dan
bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan
kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya
kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat,--tetapi kuatnya adalah
kuatnya kulit, padahal ia kosong-mlompong di bagian dalamnya.”
Bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian
dan kemandirian bangsa sendiri. Dan kepercayaan ini sangat penting,
karena menurutnya, “Sesuatu bangsa yang tidak memiliki kepercayaan
kepada diri sendiri tidak dapat berdiri langsung. A nation without faith
cannot stand.”
Beberapa puluh tahun kemudian, seorang intelektual Amerika Serikat, John
Gardner, seperti mengamini pandangan Bung Karno. Beliau menyatakan,
“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak
percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak
mengandung dimensi-dimensi moral yang dapat menopang peradaban besar
“ (Gardner, 1992)
Bagi Bangsa Indonesia, dimensi moral sebagai tumpuan karakter kolektif
yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa itu tiada lain adalah
Pancasila. Dalam pandangan Soekarno dikatakan, “...Kecuali Pancasila
adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat
mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari
Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar
Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita
letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat
mempersatu dalam perjoangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah
kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali,
Imperialisme. Perjoangan suatu bangsa, perjoangan melawan imperialisme,
perjoangan mencapai kemerdekaan, perjoangan sesuatu bangsa yang
membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara
berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri,
mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa
sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadiaan yang
terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam
perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno,
1958)
Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama itu disarikan oleh Bung Karno
pada pidato 1 Juni 1945, yang disebutnya sebagai “dasar falsafah”
(Philosofische Grondslag) atau “pandangan dunia” (Weltanschauung)
negara/bangsa Indonesia. Kelima sila, menurutnya, merupakan unsur “meja
statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus Leitstar (bintang
pimpinan) dinamis, yang memandu perkembangan bangsa ke depan.
Dengan semangat dasar kelima sila tersebut, negara/bangsa Indonesia
memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-
prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara
paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan,
antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavisitis, antara
kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara
pemerintahan autokratik dengan demokrasi pasar-individualis, antara
ekonomi etatisme dengan kapitalisme predatoris.
Diperlukan puluhan tahun sejak perang dunia kedua bagi bangsa-bangsa
lain untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia
telah meletakkannya di titik awal berdirinya Republik. Sayang, masalah
bangsa ini memang kerap pandai memulai namun gagal memelihara dan
mengakhiri. Tatkala bangsa-bangsa lain mulai mengengok warisan
pemikiran terbaik bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai
mengabaikannya.
Alhasil, tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana mencetak nilai-nilai
ideal Pancasila itu menjadi karakter kebangsaan, melalui pendalaman
pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk
mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan bidang
kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk itu, diperlukan pendekatan
sosialiasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik, meliputi dimensi
kognitif, afektif dan konatif, yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap
dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam memahami, meyakini dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut,
hendaklah diingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan
juga bintang pimpinan yang dinamis—yang mesti responsif terhadap
dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka
bagi proses pengisian dan penafsiran baru, dengan syarat memperhatikan
semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta kesalingterkaitan
antarsila. Maknanya, keterbukaan pengisian dan penafsiran atas setiap sila
Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-prinsip pokoknya dan oleh keharusan
untuk menjaga koherensinya dengan sila-sila yang lain.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada
ketaatan dari warga negara. Ketaatan kenegaraan ini, menurut Notonagoro
(1974), dapat diperinci sebagai berikut:
1.Ketaatan hukum, yang terkandung dalam pasal 27 (1) UUD 1945,
berdasarkan atas keadilan legal.
2.Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.Ketaatan keagamaan, berdasarkan atas: sila pertama Pancasila; pasal 29
(1) UUD 1945; berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga
Pembukaan UUD 1945.
4.Ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat daripada
organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat, lebih-lebih dalam
bentuk negara, organisasi hidup kesadaran dan berupa segala sesuatu yang
dapat menjadi pengalaman daripada manusia. Baik pengalaman tentang
penilaian hidup yang meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerohanian dan
religius; lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial-kultural.
Kunci ketaatan tersebut adalah semangat para penyelenggara negara dan
komitmen warga untuk menjungjung tinggi nilai-nilai keadabaan publik
berdasarkan Pancasila. Untuk itu, bukan hanya pembangunan aspek
jasmaniah yang harus diperhatikan, melainkan pertama-tama justru
pembangunan aspek kejiwaan. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!”
Itulah pesan dari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kekayaan alam
Indonesia bisa memberi kemakmuran kepada bangsa ini; namun di tangan
para penyelenggara negara yang miskin jiwa, sebanyak apapun sumber
kekayaan alam itu tak akan pernah mencukupi kesejahteraan warganya.
Kekayaan budaya Indonesia bisa memberi sumber kemajuan peradaban
kepada bangsa ini; namun di tangan para penyelenggara negara yang tak
memiliki kepercayaan diri, kekayaan budaya sebanyak apapun tak akan
pernah menjadi kekuatan kerohanian (karakter) bagi kemajuan bangsa.
Kekayaan keragaman Indonesia bisa memberi landasan kehidupan yang
rukun dan saling menyempurnakan; namun di tangan para penyelenggara
negara yang kerdil, kekayaan keragaman itu menjadi sumber pertikaian dan
saling mengucilkan.
Dalam kaitan ini, peringatan Wiranatakoesoema pada sidang BPUPK seperti
mengantisipasi kemungkinan ini:
Pada hemat saya hal yang menyedihkan ini disebabkan karena manusia
tidak atau tidak cukup menerima latihan batin, ialah latihan yang
menimbulkan dalam sanubarinya suatu kekuatan yang menggerakkan ia
(motive force) untuk mengenal kebenarannya dan menerima macam-macam
pertanggungan jawab sebagai seorang anggota masyarakat yang
aktif,...bukankah tujuan kita pro patria. Tetapi pro patria per orbis
concordiam. Maka alam moral ini hendaknya kita pecahkan, karena latihan
otak (intellect) saja, betapa besarnya juga, sungguh tak akan mencukupi
untuk menjadikan manusia menjadi anggota masyarakat yang baik.
Dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam
realitas, kita perlu menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti
yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri.
Fitrah pertama adalah semangat ”menuhan” (ketakwaan kepada Tuhan).
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sikap ”ihsan”
dengan mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai ”Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Dengan pengakuan ini, menurut Bung
Hatta, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia, untuk mewujudkan
suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul
dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan
sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua,
Tuhan Yang Maha Kuasa.
Fitrah kedua adalah semangat kekeluargaan. Dalam pidato tentang
Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan:
Kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya.
Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam
buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat
Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat
Indonesia—semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga,
dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia
yang tulen, yaitu perkataan „Gotong-royong‟. Negara Indonesia yang kita
dirikan haruslah Negara gotong-royong!
Fitrah ketiga adalah semangat keikhlasan dan ketulusan. Dalam mengambil
keputusan yang sulit, seperti dalam menentukan bentuk negara (uni,
federasi atau konfederasi), para pendiri bangsa di BPUPK terlebih dahulu
mengheningkan cipta seraya memanjatkan do‟a agar keputusan yang
diambil dilandasi maksud yang suci dan diterima dengan hati yang murni
dengan penuh keikhlasan.
Fitrah keempat adalah semangat pengabdian dan tanggung jawab. Dalam
membincangkan hukum dasar, Muhammad Yamin mengingatkan, ”Saya
hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak
rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan
daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-
Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak
daripada republik.”
Fitrah kelima adalah semangat menghasilkan yang terbaik. Menanggapi
Soepomo, yang menyatakan bahwa tidak bisa dibentuk hukum dasar yang
sempurna di masa perang, Soekarno mengingatkan, ”Saya peringatkan
tentang lamanya perang kita tidak tahu, barangkali satu bulan barangkali
lebih lama dan jikalau hukum dasar kurang sempurna, lebih baik didekatkan
pada kesempurnaan.”
Fitrah keenam adalah semangat keadilan dan kemanusiaan. Dalam
Pancasila, kata „keadilan‟ ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila
sekaligus. Pada sila kedua, keadilan dijadikan landasan nilai perjuangan
kemanusiaan; pada sila kelima, keadilan itu dijadikan tujuan perjuangan.
Bung Hatta mengingatkan: “Camkanlah, negara Republik Indonesia belum
lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum
sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat
melaksanakan pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.”
Fitrah ketujuh adalah semangat kejuangan. Dalam pandangan Bung Hatta,
sebuah bangsa tidaklah eksis dengan sendirinya, melainkan tumbuh atas
landasan suatu keyakinan, sikap batin yang memancarkan etos kejuangan
yang perlu dibina dan dipupuk sepanjang masa. “Bagi kami, Indonesia
menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-
citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap
orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”
Fitrah dasar kehidupan bernegara itu perlu dihidupkan sebagai tenaga batin
dan prasyarat moralitas yang dapat mengangkat marwah bangsa dari
kerendahannya. Dalam peringatan Isra Mi‟raj 7 Februari 1959, Soekarno
mengingatkan:
Tidak ada suatu bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya tidak terbuat dari
nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal,
kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang ingin Mi‟raj—kenaikan ke
atas, supaya kebudayaan kita naik ke atas, supaya negara kita naik ke atas.
Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng untuk naik ke atas, bangsa
yang demikian itu, dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka
bumi (sirna ilang kertaning bumi).
Demikianlah, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat,
alasan, dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya.
Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan
ekonomi atau kehilangan pemimpin, melainkan kehilangan karakter dan
harga diri, karena diabaikannya semangat dasar kehidupan bernegara. “Aib
terbesar,” kata Juvenalis, “ketika kamu lebih mementingkan kehidupan
ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah
kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”
Membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama,
mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tak hanya jadi retorika atau
verbalisme di pentas politik. Karena itu, rejuvenasi Pancasila harus
dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar
falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah,
mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundangan,
koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan
menjadikannya sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama.
Marilah kita muliakan nilai-nilai Pancasila sebagai kunci kemajuan bangsa.
Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Pengalaman
menjadi Indonesia menunjukkan bahwa spirit perjuangan memiliki
kemampuan yang tak terbatas untuk menghadapi berbagai rintangan karena
adanya harapan. Kemarahan, ketakutan dan kesedihan memang tak
tertahankan, tetapi sejauh masih ada harapan semangat tetap menyala.
Harapan yang positif bukanlah khayalan kosong, melainkan harapan yang
berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa
visi bisa membawa kesesatan. Upaya menyemai politik harapan harus
memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu,
peluang masa kini, dan keampuhannya mengantisipasi masa depan. Dalam
kerangka itulah, penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan
mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi
masalah kekinian adalah cara tepat untuk mentransformasikan ketakutan
menjadi harapan.
Indonesia adalah satu-satunya negeri di muka bumi yang menyebut
negerinya dengan „tanah air‟. Selama masih ada lautan yang bisa dilayari,
dan selama masih ada tanah yang bisa ditanami, selama itu pula masih ada
harapan. Selamat berjuang! Ingatlah pesan Bung Karno, ijazah boleh robek
dan hancur, tetapi karakter Pancasila tak boleh lekang. Itulah modal
permanen bagi kehidupan dan kemajuan!
Basis Karakter Kemajuan (2)
Wednesday, 24 September 2014, 10:38 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/09/24/ncdzfg-basis-karakter-kemajuan-2
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Dalam Amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan
pentingnya bangsa memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar
kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa.
”Bangsa Indonesia harus mempunyai isi-hidup dan arah-hidup. Kita harus
mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai
isi-hidup dan arah-hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa
yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak
mempunyai levensdiepte sama sekali.”
“Ia adalah bangsa penggemar emas sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia
mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada
gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-
kadang kuat—tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong
melompong di bagian dalamnya."
“Bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada nilai-nilai kepribadian
dan kemandirian bangsa sendiri. Dan kepercayaan ini sangat penting,
karena menurutnya, „Sesuatu bangsa yang tidak memiliki kepercayaan
kepada diri sendiri tidak dapat berdiri langsung. A nation without faith
cannot stand."
Beberapa puluh tahun kemudian, seorang intelektual Amerika Serikat, John
Gardner, seperti mengamini pandangan Bung Karno. Beliau menyatakan,
“Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak
percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak
mengandung dimensi-dimensi moral yang dapat menopang peradaban
besar.“ (Gardner, 1992).
Bagi bangsa Indonesia, dimensi moral sebagai tumpuan karakter kolektif
yang dapat menopang kemajuan peradaban bangsa itu tiada lain adalah
Pancasila. Dalam pandangan Soekarno dikatakan, "... Kecuali Pancasila
adalah satu weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat
mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari
Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar
Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita
letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat
mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah
kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali,
imperialisme.
“Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan
mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak
sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-
tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik
sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai
kepribadian sendiri. Kepribadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam
kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain
sebagainya.” (Soekarno, 1958).
Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama itu disarikan oleh Bung Karno
pada pidato 1 Juni 1945, yang disebutnya sebagai “dasar falsafah”
(philosofische grondslag) atau “pandangan dunia” (weltanschauung)
negara/bangsa Indonesia. Kelima sila, menurutnya, merupakan unsur “meja
statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus leitstar (bintang
pimpinan) dinamis, yang memandu perkembangan bangsa ke depan.
Dengan semangat dasar kelima sila tersebut, negara/bangsa Indonesia
memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting. Prinsip-
prinsip dalam Pancasila mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan antara
paham kenegaraan radikalisme sekularis dan radikalisme keagamaan,
antara paham kebangsaan homogenis dengan tribalisme atavisitis, antara
kebangsaan yang chauvinis dengan globalisme triumphalis, antara
pemerintahan autokratik dan demokrasi pasar-individualis, antara ekonomi
etatisme dan kapitalisme predatoris.
Diperlukan puluhan tahun sejak Perang Dunia II bagi bangsa-bangsa lain
untuk memasuki jalan tengah keemasan itu. Adapun bangsa Indonesia telah
meletakkannya di titik awal berdirinya Republik. Sayang, masalah bangsa ini
memang kerap pandai memulai, tapi gagal memelihara dan mengakhiri.
Tatkala bangsa-bangsa lain mulai menengok warisan pemikiran terbaik
bangsa ini, bangsa Indonesia sendiri mulai mengabaikannya.
Alhasil, tantangan bangsa Indonesia adalah bagaimana mencetak nilai-nilai
ideal Pancasila itu menjadi karakter kebangsaan melalui pendalaman
pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk
mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan bidang
kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk itu, diperlukan pendekatan
sosialisasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik, meliputi dimensi
kognitif, afektif, dan konatif yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap,
dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam memahami, meyakini dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut,
hendaklah diingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan
juga bintang pimpinan yang dinamis—yang mesti responsif terhadap
dinamika perkembangan zaman.
Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka bagi proses pengisian dan penafsiran
baru, dengan syarat memperhatikan semangat dasar yang terkandung di
dalamnya serta kesalingterkaitan antarsila. Maknanya, keterbukaan
pengisian dan penafsiran atas setiap sila Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-
prinsip pokoknya dan oleh keharusan untuk menjaga koherensinya dengan
sila-sila yang lain.
Basis Karakter Kemajuan (3) Rabu, 01 Oktober 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/09/30/ncpwh9-basis-karakter-kemajuan-3
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada
ketaatan dari warga negara. Ketaatan kenegaraan ini, menurut Notonagoro
(1974), dapat diperinci sebagai berikut.
Pertama, ketaatan hukum yang terkandung dalam Pasal 27 (1) UUD 1945
berdasarkan atas keadilan legal. Kedua, ketaatan kesusilaan berdasarkan
atas sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, ketaatan keagamaan berdasarkan atas sila pertama Pancasila, Pasal
29 (1) UUD 1945, berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga
Pembukaan UUD 1945. Keempat, ketaatan mutlak atau kodrat atas dasar
bawaan kodrat daripada organisasi hidup bersama dalam bentuk
masyarakat, lebih-lebih dalam bentuk negara, organisasi hidup kesadaran
dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengalaman daripada
manusia. Baik pengalaman tentang penilaian hidup yang meliputi lingkungan
hidup kebendaan, kerohanian, dan religius; lingkungan hidup sosial
ekonomis, sosial politis, dan sosial-kultural.
Kunci ketaatan tersebut adalah semangat para penyelenggara negara dan
komitmen warga untuk menjungjung tinggi nilai-nilai keadaban publik
berdasarkan Pancasila. Untuk itu, bukan hanya pembangunan aspek
jasmaniah yang harus diperhatikan, melainkan pertama-tama justru
pembangunan aspek kejiwaan.
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!” Itulah pesan dari lagu
Kebangsaan Indonesia Raya. Kekayaan alam Indonesia bisa memberi
kemakmuran kepada bangsa ini, tapi di tangan para penyelenggara negara
yang miskin jiwa, sebanyak apa pun sumber kekayaan alam itu tak akan
pernah mencukupi kesejahteraan warganya.
Kekayaan budaya Indonesia bisa memberi sumber kemajuan peradaban
kepada bangsa ini, tapi di tangan para penyelenggara negara yang tak
memiliki kepercayaan diri, kekayaan budaya sebanyak apa pun tak akan
pernah menjadi kekuatan kerohanian (karakter) bagi kemajuan bangsa.
Kekayaan keragaman Indonesia bisa memberi landasan kehidupan yang
rukun dan saling menyempurnakan, tapi di tangan para penyelenggara
negara yang kerdil, kekayaan keragaman itu menjadi sumber pertikaian dan
saling mengucilkan.
Dalam kaitan ini, peringatan Wiranatakoesoema pada sidang BPUPK seperti
mengantisipasi kemungkinan ini: Pada hemat saya hal yang menyedihkan ini
disebabkan oleh manusia tidak atau tidak cukup menerima latihan batin,
ialah latihan yang menimbulkan dalam sanubarinya suatu kekuatan yang
menggerakkan ia (motive force) untuk mengenal kebenarannya dan
menerima macam-macam pertanggungjawaban sebagai seorang anggota
masyarakat yang aktif ... bukankah tujuan kita pro patria. Tetapi, pro patria
per orbis concordiam. Maka, alam moral ini hendaknya kita pecahkan karena
latihan otak (intellect) saja, betapa besarnya juga, sungguh tak akan
mencukupi untuk menjadikan manusia menjadi anggota masyarakat yang
baik.
Dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam
realitas, kita perlu menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti
yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri. Fitrah
pertama adalah semangat ”menuhan” (ketakwaan kepada Tuhan).
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sikap ”ihsan”
dengan mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai ”Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Dengan pengakuan ini, menurut Bung
Hatta, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan
suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul
dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan
sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua,
Tuhan Yang Maha Kuasa.
Fitrah kedua adalah semangat kekeluargaan. Dalam pidato tentang
Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan: Kita mendirikan Negara
Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua!
Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan
Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan
Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia --
semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang
tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen,
yaitu perkataan „gotong-royong‟. Negara Indonesia yang kita dirikan
haruslah negara gotong-royong!
Fitrah ketiga adalah semangat keikhlasan dan ketulusan. Dalam mengambil
keputusan yang sulit, seperti dalam menentukan bentuk negara (uni,
federasi, atau konfederasi), para pendiri bangsa di BPUPK terlebih dahulu
mengheningkan cipta seraya memanjatkan doa agar keputusan yang diambil
dilandasi maksud yang suci dan diterima dengan hati yang murni dengan
penuh keikhlasan. Fitrah keempat adalah semangat pengabdian dan
tanggung jawab
Basis Karakter Kemajuan (4) Wednesday, 08 October 2014, 06:00 WIB
SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/08/nd2yc4-basis-karakter-kemajuan-4
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yudi Latif
Dalam membincangkan hukum dasar, Muhammad Yamin mengingatkan,
”Saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak
rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan
daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-
Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak
daripada republik.”
Fitrah kelima adalah semangat menghasilkan yang terbaik. Menanggapi
Soepomo yang menyatakan bahwa tidak bisa dibentuk hukum dasar yang
sempurna di masa perang, Sukarno mengingatkan, ”Saya peringatkan
tentang lamanya perang kita tidak tahu, barangkali satu bulan barangkali
lebih lama dan jikalau hukum dasar kurang sempurna, lebih baik didekatkan
pada kesempurnaan.”
Fitrah keenam adalah semangat keadilan dan kemanusiaan. Dalam
Pancasila, kata “keadilan” ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila
sekaligus. Pada sila kedua, keadilan dijadikan landasan nilai perjuangan
kemanusiaan. Pada sila kelima, keadilan itu dijadikan tujuan perjuangan.
Bung Hatta mengingatkan, “Camkanlah, negara Republik Indonesia belum
lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum
sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat
melaksanakan Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.”
Fitrah ketujuh adalah semangat kejuangan. Dalam pandangan Bung Hatta,
sebuah bangsa tidaklah eksis dengan sendirinya, melainkan tumbuh atas
landasan suatu keyakinan, sikap batin yang memancarkan etos kejuangan
yang perlu dibina dan dipupuk sepanjang masa. “Bagi kami, Indonesia
menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-
citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap
orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”
Fitrah dasar kehidupan bernegara itu perlu dihidupkan sebagai tenaga batin
dan prasyarat moralitas yang dapat mengangkat marwah bangsa dari
kerendahannya. Dalam peringatan Isra Mi'raj 7 Februari 1959, Sukarno
mengingatkan, "Tidak ada suatu bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya
tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa
Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang
ingin Mi'raj-kenaikan ke atas, supaya kebudayaan kita naik ke atas, supaya
negara kita naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng
untuk naik ke atas, bangsa yang demikian itu dengan sendirinya akan gugur
pelan-pelan dari muka bumi (sirna ilang kertaning bumi)."
Demikianlah, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat,
alasan, dan tujuan perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhurnya.
Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan
ekonomi atau kehilangan pemimpin, melainkan kehilangan karakter dan
harga diri karena diabaikannya semangat dasar kehidupan bernegara. “Aib
terbesar,” kata Juvenalis, “ketika kamu lebih mementingkan kehidupan
ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah
kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”
Membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama,
mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tak hanya jadi retorika atau
verbalisme di pentas politik. Karena itu, rejuvenasi Pancasila harus
dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar
falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah,
mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundangan,
koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial, dan
menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, dan komitmen bersama.
Marilah kita muliakan nilai-nilai Pancasila sebagai kunci kemajuan bangsa.
Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Pengalaman
menjadi Indonesia menunjukkan bahwa spirit perjuangan memiliki
kemampuan yang tak terbatas untuk menghadapi berbagai rintangan karena
adanya harapan. Kemarahan, ketakutan, dan kesedihan memang tak
tertahankan, tetapi sejauh masih ada harapan, semangat tetap menyala.
Harapan yang positif bukanlah khayalan kosong, melainkan harapan yang
berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa
visi bisa membawa kesesatan. Upaya menyemai politik harapan harus
memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan, baik masa lalu,
peluang masa kini, dan keampuhannya mengantisipasi masa depan. Dalam
kerangka itulah, penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan
mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi
masalah kekinian adalah cara tepat untuk mentransformasikan ketakutan
menjadi harapan.
Indonesia adalah satu-satunya negeri di muka bumi yang menyebut
negerinya dengan “tanah air”. Selama masih ada lautan yang bisa dilayari,
dan selama masih ada tanah yang bisa ditanami, selama itu pula masih ada
harapan. Selamat berjuang! Ingatlah pesan Bung Karno, ijazah boleh robek
dan hancur, tetapi karakter Pancasila tak boleh lekang. Itulah modal
permanen bagi kehidupan dan kemajuan!
Islam Dalam Krisis (1)
Selasa, 09 Desember 2014, 06:00 WIB SUMBER : http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/12/08/ng9s7l-islam-dalam-krisis-1
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Professor Ahmad Syafii Maarif
Jika turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi sebagai awal kenabian
dapat diterima menjadi tonggak karier Islam di muka bumi, maka karier itu
sudah berlangsung dalam lipatan abad yang panjang. Islam bukan lagi
agama sederhana, ia sudah kompleks sekali. Tafsiran terhadap agama
terakhir ini sudah berlapis-lapis, sehingga untuk menentukan mana yang
emas dan mana yang loyang menjadi tidak mudah, kecuali di tangan orang
yang dikurniai „aqlun shaĥîh wa qalbun salîm (minda yang sehat tak terbelah
dan hati yang tulus tanpa cacat), sekalipun tidak pernah sempurna. Alquran
pasti membuka diri terhadap orang dengan kualitas prima ini. Tetapi
manusia tetap manusia dengan segala keterbatasannya, ada saja sisi-sisi
yang lemah yang mengganggu.
Dari sudut pandang relativisme manusia inilah kita harus memahami
mengapa telah berlaku peperangan antara kelompok „Aisyah binti Abû Bakr,
janda nabi, yang dipimpin oleh Thalĥâh bin „Ubaidillâh dan Zubair bin
„Awwâm berhadapan dengan pendukung Khalifah „Alî bin Abî Thâlib (656-
661), sepupu dan menantunya. Menurut hadist, sebagai sahabat nabi,
mereka yang terlibat dalam peperangan ini telah dijamin masuk surga. Ini
adalah krisis politik pertama yang berdarah dalam sejarah Islam yang
dikenal dengan Perang Onta, terjadi tahun 35 H/656 M, segera setelah
berlaku pembunuhan keji atas diri Khalifah „Ustmân bin „Affân (644-656)
oleh pemberontak Muslim yang menentang kebijakan khalifah yang dinilai
tidak adil.
Krisis kedua yang lebih dahsyat di periode awal itu terjadi dalam perang
Shiffîn (657) antara pasukan‟Ali dan Mu‟awiyyah bin Abû Sufyân, gubernur
Suria yang diangkat Khalifah „Umar bin Kaththâb (632-644) di masa
kekhalifahannya. Dalam perang saudara yang masih dikait-kaitkan dengan
Parang Onta ini, ribuan yang mati dari kedua pihak. Ketika pasukan „Alî
nyaris menang, utusannya Abû Mûsâ al-„Asy‟arî ditipu oleh utusan
Mu‟âwiyah, „Amr bin „Ash yang cerdik, agar peperangan dihentikan dan
berdamai (taĥkîm) di Daumatul Jandal, sebuah oase di lembah Sirhan yang
terletak antara Damaskus dan Madinah.
Peluang ini digunakan dengan licik oleh „Amr bin „Ash untuk mengganti „Alî
sebagai khalifah dengan menobatkan Mu‟âwiyah, idolanya. Tetapi kekuasaan
penuh Mu‟awiyah harus menanti dulu kematian „Ali karena ditikam oleh
mantan pengikutnya di masjid Kufah. Kelompok garis keras ini kemudian
dikenal dalam sejarah sebagai golongan khawarij (yang memisahkan diri)
dari „Ali karena menentang taĥkîm di Daumatul Jandal. Tetapi sebenarnya
yang tetap setia kepada „Ali sampai detik terakhir adalah kaum Anshar.
Adapun orang Iraq dan apa yang dikenal dengan golongan al-Qurra tidak
sepenuh hati mendukung „Ali. Kelemahan ini dibaca dan dimanfaatkan oleh
pihak Mu‟awiyah untuk memecah belah kubu „Ali dan berhasil.
Saya rekamkan kejadian tragis ini bukan untuk membuka luka yang telah
berusia belasan abad, tetapi untuk menyadarkan kita semua bahwa
sengketa yang berdarah-darah di atas sepenuhnya adalah gejala Arab,
bukan mewakili Alquran yang dengan tegas memerintahkan agar orang
beriman itu bersaudara dan berdamai. (Lih. Aquran . Al-Ĥujurât: 10).
Ironisnya adalah perpecahan yang bercorak Arab ini kita warisi sampai detik
ini. Seakan-akan kelakuan para sahabat yang terlibat dalam sengketa dan
peperangan itu menjalankan perintah Alquran, sama sekali tidak. Adapun
mereka itu dijamin masuk surga sepenuhnya adalah urusan Allah dengan
mereka, kita tidak tahu.
Dari tragedi Shiffîn inilah kemudian berkembang tiga faksi besar umat yang
tidak pernah berdamai: sunni, syi‟ah, dan khawarij. Sunni yang muncul
sebagai golongan mayoritas merasa diri selalu berada di pihak yang benar
dengan menuduh kelompok syi‟ah dan khawarij sebagai pihak yang salah.
Cara pandang yang semacam ini harus dihalau jauh-jauh dengan
menjadikan Alquran sebagai hakim dan rujukan yang tertinggi. Kepentingan
politik sesaat dengan dalil agama sekalipun bagi saya adalah sebuah
pengkhianatan. Sunni, syi‟ah, dan khawarij adalah buah dari perpecahan
politik, mengapa kemudian diberhalakan? Pemberhalaan inilah yang selama
ratusan tahun telah menghancurkan persaudaraan sejati umat Islam,
termasuk umat Islam yang tidak ada hubungannya dengan yang budaya
Arab yang suka berpecah belah itu.
Reference sites
1. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/17/nf6t6m-
patriotisme
2. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/14/nf17sj-
terusiknya-kedaulatan-kita
3. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/12/nexo2r-
suatu-hari-di-kampung-tatar
4. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/10/netyus-
budaya-politik-indonesia
5. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/07/neo60y-pahlawan-dan-kita
6. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/06/nemd5o-
mobil-amien-rais-ditembak
7. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/05/neka26-
masjid-cordova
8. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/03/neh0m1-
tukang-cat
9. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/10/31/neb6a4-
sumpah-pemuda-dan-bola-indonesia
10. http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/11/03/neh0m1-
tukang-cat