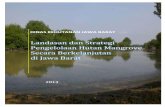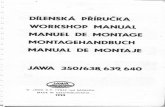peran kyai dalam penanaman kecerdasan spiritual santri di ...
konsep kepemimpinan islam-jawa dalam manuskrip kyai
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of konsep kepemimpinan islam-jawa dalam manuskrip kyai
KONSEP KEPEMIMPINAN ISLAM-JAWA DALAM MANUSKRIP KYAI
AGENG IMAM PURO DAN RELEVANSINYA DENGAN
KEPEMIMPINAN PUBLIK DI INDONESIA
TESIS
Oleh:
HERU BUDI SUSENO
NIM 502200012
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022
SURAT PERSETUJUAN
PUBLIKASI
Yang Bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Heru Budi Suseno
NIM : 210415008
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Konsep Kepemimpinan Islam-Jawa DalamManuskrip Kyai
Ageng Imam Puro dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan
Publik
Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh
perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.
Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari
penulis.
Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.
Ponorogo 13 Juni 2022
Penulis
Heru Budi Suseno
NIM. 502200012
PERSEMBAHAN
Tesis ini dipersembahkan untuk:
Bapak, Ibu, kakak dan Adik-adik Ku
Setiap bulu, kulit, daging, urat, tulang, otak, dan ruhku berdoa dalam bakti
kehidupan. Harapan yang kalian alirkan dalam denyut darah dan doa yang
kalian taburkan pada nafas adalah jantung masa depan, yang aku hidup
bersamanya.
Guru-guruku
Nafas ilmu, denyut kesalehan, dan gerak langkah ajaran aku baca sampai
lembar-lembar terakhir kehidupan.
Sahabat-sahabatku
Kalian adalah sosok-sosok penting yang menghiasi hari-hariku. tak akan indah
kehidupan ini tanpa keceriaan, senyuman, dan kebersamaan bersama kalian.
Almamater tercinta
IAIN Ponorogo
MOTTO
“Urip Kang Utama, Mateni Kang Sempurna”
Selama Hidup Kita Melakukan Perbuatan Baik Maka Kita Akan Menemukan
Kebahagiaan di Kehidupan Selanjutnya
“Yen Urip Mung Isine Isih Nuruti Napsu, Sing Jenenge Kamulyan Mesti Soyo
Angel Ketemu”
Jika Hidup Masih Dipenuhi Dengan Nafsu Untuk Bersenang-Senang,Yang
Namanya Kemuliaan Hidup Akan Semakin Sulit Ditemukan
ABSTRAK
Heru Budi Suseno. 2022. Konsep Kepemimpinan Islam-Jawa Dalam Manuskrip
Kyai Ageng Imam Puro dan Relevansinya Dengan Kepemimpinan
Publik. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Nur Kolis, Ph.D
Kata Kunci : Kyai Ageng Imam Puro, Naṣāiḥ al-Mulūk, Adāb al-Mulūk, Adāb
al-Salāṭīn, Kepemimpinan Islam-Jawa.
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro merupakan salah satu karya sastra
Jawa yang membahas tentang kepemimpinan Islam-Jawa. Kyai Ageng Imam Puro
merupakan seorang ulama Ponorogo yang punya kredibilitas tinggi dan wawasan
yang luas, ditambah lagi dengan konteks sosial politik nusantara waktu itu dan
dengan latar belakang dan sejarah penulisan yang kompleks menjadi sangat
menarik untuk dibahas.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi manuskrip Kyai
Ageng Imam Puro (2) menganalisis konsep kepemimpinan Islam-Jawa dalam
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro, dan (3) menganalisis relevansi kepemimpinan
publik dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro. Menggunakan metode filologi
yang terdiri dari: (1) inventarisasi naskah, (2) deskripsi naskah, (3) suntingan teks,
(4) terjemahan teks, dan (5) analisis isi. Teori yang digunakan diantaranya: (1)
hermeneutika double movement, dan (2) interaksionisme-simbolik.
Berdasarkan analisis terhadap Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
mempunyai keistimewaan yang luar biasa dalam menguraikan masalah
kepemimpinan diantaranya pertama, dari sisi sajian redaksi kalimatnya yang
kental nuansa sastra. Kedua, referensi naskah yang otentik. Ketiga,
kontekstualisasi dengan kondisi keindonesiaan khususnya Jawa. Dalam
menguraikan kepemimpinan Islam-Jawa Kyai Ageng Imam Puro ditulis menjadi 2
bab pertama, bab Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk (Integritas Moral Pemimpin) berisi
tentang kepemimpin adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh
pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kedua,
Kitab Adāb al-Mulūk (Karatkter Ideal Pemimpin) inti bab ini adalah kualitas
kepribadian pemimpin merupakan hal yang paling ideal dan penting dimilliki oleh
seorang pemimpin. Terdapat 10 kriteria seorang pemimpin menurut Kyai Ageng
Imam Puro antara lain : Berakal Sehat dan Berbudi Syariat, Berilmu/ Cerdas :
Fathanah, Aqil Baligh, Budi Pekerti Baik, Peduli : Empati, Welas Asih, Berani,
Mengurangi Makan dan Tidur, Menahan Hawa Nafsu, Pemimpin Laki-laki.
Dalam menguraikan relevansi kepemimpinan publik dengan Kyai Ageng
Imam Puro ini ada tiga argumentasi yang memiliki arti penting dalam konteks
kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi.
Komponen kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam
kebijakan pemerintah dalam mendukung program modernisasi. Kepemimpinan
terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan
publik memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras
dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan
kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik.
ABSTRACT
Heru Budi Suseno. 2022. The Concept of Javanese-Islamic Leadership in Kyai
Ageng Imam Puro's Manuscript and Its Relevance to Public
Leadership. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Nur Kolis,
Ph.D
Kata Kunci : Kyai Ageng Imam Puro, Naṣāiḥ al-Mulūk, Adāb al-Mulūk, Adāb
al-Salāṭīn, Leadership Islamic-Javanese.
The Kyai Ageng Imam Puro manuscript is a Javanese literary work that
discusses Javanese-Islamic leadership. Kyai Ageng Imam Puro is a Ponorogo
cleric who has high credibility and broad insight, coupled with the socio-political
context of the archipelago at that time and with a complex background and history
of writing, it becomes very interesting to discuss.
This study aims to: (1) identify the Kyai Ageng Imam Puro manuscript (2)
analyze the concept of Javanese-Islamic leadership in the Kyai Ageng Imam Puro
Manuscript, and (3) analyze the relevance of public leadership in the Kyai Ageng
Imam Puro Manuscript. Using a philological method consisting of: (1) manuscript
inventory, (2) manuscript description, (3) text editing, (4) text translation, and (5)
content analysis. The theories used include: (1) double movement hermeneutics,
and (2) symbolic-interactionism.
Based on an analysis of the Kyai Ageng Imam Puro Manuscript, he has
extraordinary features in describing leadership problems, first of all, from the
editorial side of his sentence which is thick with literary nuances. Second,
authentic manuscript references. Third, contextualization with Indonesian
conditions, especially Java. In describing the Javanese-Islamic leadership of Kyai
Ageng Imam Puro, it is written into the first 2 chapters, the chapter Kitāb Naṣāiḥ
al-Mulūk (The Moral Integrity of Leaders) contains about leadership is the
process of influencing or setting an example by the leader to his followers in an
effort to achieve organizational goals. Second, Kitab Adab al-Mulūk (Ideal
Character of Leaders) the core of this chapter is that the personality quality of a
leader is the most ideal and important thing for a leader to have. There are 10
criteria for a leader according to Kyai Ageng Imam Puro, among others:
Reasonable and virtuous Shari'a, Knowledgeable / Intelligent: Fathanah, Aqil
Baligh, Good manners, Caring: Empathy, Compassionate, Courageous, Reduce
eating and sleep, Retaining Lust, Male Leader.
In outlining the relevance of public leadership with Kyai Ageng Imam
Puro, there are three arguments that have important meaning in the context of
leadership. First, strong leadership to collaborate. The key component of public
leadership appears to be emerging in government policies in support of
modernization programs. Leadership looks strong to encourage collaborative
ministry. Second, public leadership has the potential to generate new knowledge
that aligns with complexity. Third, there is sufficient room to increase leadership
in development across the public sector.
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan semesta Alam, Sang
penggenggan jiwa, Dzat Yang Maha Sempurna, Allah SWT, yang senantiasa
mengalirkan Rohman-RohimNya kepada kami yang tengah berada dalam fase
bertolabul ‘ilmi. Wa al-Shalātu wa al-Salāmu ‘alā Rasūlillāh, doa tulusku
untukmu wahai Rasulullah saw, para keluarga, sahabat, tabi’in, serta pengikut
terbaikmu.
Tesis ini membahas tentang “Konsep Kepemimpinan Islam-Jawa Dalam
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dan Implementasi Kepemimpinan Publik di
Indonesia”, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan dekat dalam
kekurangan. Oleh karena itu, tesis ini sangat terbuka untuk dikoreksi dan
mendapatkan masukan dari pembaca. Disamping itu, Penelitian tidak berarti apa-
apa tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan selesainya tesis
ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kami sampaikan
kepada:
1. Ibu Dr. Hj. Evi Muafiah M.Ag selaku rektor IAIN Ponorogo
2. Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN
Ponorogo.
3. Bapak Dr. Sugiyar, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam
IAIN Ponorogo beserta stafnya.
4. Bapak Nur Kolis, Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis atas bimbingan
dan dukungannya serta keluangan waktu, kecermatan dan kebijaksanaan
beliau tesis ini terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen MPI, karyawan dan karyawati serta seluruh civitas
akademika, lingkungan Pascasarjan IAIN Ponorogo.
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian KH. Muhammad Maksum, K.
Muhammad Fatuhat, Mas Rofiqi yang telah bersedia meluangkan waktu,
membantu dan memberikan dukungan penulis selama menyelesaikan
penelitian.
7. Kedua orangku, Bapak Lasimun dan Ibu Supatmi yang telah membimbing
dan mengajarkan etika, tiada kata lain selain ucapan do’a yang selalu buat
kalian, terimah kasih atas motivasi hidup yang kalian berikan kepadaku.
Semoga Bapak Lasimun dan Ibu Supatmi diberikan umur yang panjang
dan barokah, serta kesehatan. Amin
8. Terima kasih juga kepada kakak ku tersayang Khusnul Khotimah dan
adik-adiku Heri Prayitno dan Alif Thoriqul Huda, yang selalu dan selalu
memotivasi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun. Semoga kalian
diberikan rizki yang banyak, halal dan berkah, serta kesehatan dan umur
yang panjang. Amin.
9. Keluarga besar MPI.B angkatan tahun 2020 yang selalu menyemangati
dan yang selalu menghibur. Terimahkasih atas segalanya.
10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat. Terima Kasih
banyak.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tanpa doa dan
motivasi kalian semua, mungkin tidak akan selesai. Oleh karena itu, saya
mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan apabila ada kritik dan saran yang
membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca
dan semua pihak yang membutuhkannya.
Ponorogo, 2 Juni 2022
Penulis,
Heru Budi Suseno
NIM.502200012
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
LEMBAR PERSETUJUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii
LEMBAR PENGESAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii
PERNYATAAN KEASLIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
PEDOMAN TRANSELITERASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ix
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
E. Kajian Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
F. Kerangka Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
G. Metode Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
H. Sistematika Pembahasan . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
BAB II : KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN
A. Kepemimpinan Publik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
B. Kepemimpinan Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
C. Kepemimpinan Jawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BAB III : MANUSKRIP KYAI IMAM PURO
A. Biografi Kyai Ageng Imam Puro . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B. Identifikasi Naskah Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro . . . . . . . . 40
C. Ringkasan Isi Naskah Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro . . . . . . .46
D. Suntingan Naskah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
E. Terjemahan Naskah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
BAB IV : KONSEP KEPEMIMPINAN ISLAM-JAWA DALAM
MANUSKRIP KYAI AGENG IMAM PURO
A. Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk (Integritas Moral Pemimpin). . . . . . . . . . . 54
B. Kitab Adāb al-Mulūk (Karatkter Ideal Pemimpin) . . . . . . . . . . . . . 56
C. Kitab Adāb al-Salāṭīn (Manajemen Kepemimpinan) . . . . . . . . . . . 63
BAB V : RELEVANSI KEPEMIMPINAN PUBLIK DI INDONESIA
DALAM MANUSKRIP KYAI AGENG IMAM PURO
A. Potret Kepimpinan Publik Di Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
B. Karakter Pemimpin Sejati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
C. Kepemimpinan Publik Masa Depan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
BAB VI : PENUTUP
A. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .78
B. Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BIOGRAFI PENULIS
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejarah umat manusia mencatat bahwa sejak zaman dahulu manusia yang hidup
berkelompok sudah mengenal istilah kepemimpinan. Kepemirnpinan rnerupakan aspek penting bagi
seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya
untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kepemimpinan memiliki peranan strategis dalam
kerangka manajemen, sebab peranan seorang pemimpin pada dasarnya merupakan serangkaian
fungsi kepemimpinan. Sedangkan fungsi kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu di antara
peranan manajer dalam kerangka untuk mempengaruhi bawahan atau pengikutnya agar dengan
penuh kemauan memberikan pengabdian dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan
kemampuan bawahan secara maksimal. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen inilah manajemen
organisasi harus dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui
pendayagunaan fungsi-fungsi manajemen yaitu meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengontrolan (controlling).1
Faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin di antaranya adalah teknik kepemimpinan,
yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang
dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh seorang
pemimpin. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung bagaimana
kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi
dan kondisi dalam organisasi tersebut.2 Dalam perkembangannya belakangan ini, kepemimpinan
dianggap sebagai suatu yang sangat memprihatinkan terutama dengan kecenderungan sejumlah
besar pemimpin pada level pemimpin organisasi formal yang cenderung corrupt. Akibatnya
kepemimpinan dicitrakan sebagai sesuatu yang kotor, nista dan mengambil keuntungan di satu
pihak tetapi merugikan dipihak lain. Orang kemudian tidak jarang miris melihat organisasi sebagai
sarang korupsi dengan bentuknya yang beragam. Di dunia birokrasi, kepemimpinan sering diklaim
dengan isu money politik, korupsi dan nepotisme. 3
Dalam konteks ke Indonesiaan, krisis keteladanan sosial (social distrust) saat ini menjadikan
bangsa ini kehilangan figur yang patut menjadi contoh dan teladan yang harus diikuti secara
konsisten. Oleh karenanya, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menerjemahkan
1 Hardi Mulyono, “Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan
Tinggi” Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3. No. 1 (2018): 294 2 Marsetio, Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership (Bogor: Univ. Pertahanan, 2018): 61
3 Berliana Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer (Jakarta: PT Mizan Publika,
2006): 7
2
nilai-nilai keadilan dalam praksis kehidupan. Orang-orang yang dipimpin harus mendapatkan rasa
adil dan kesejahteraan lahir dan batin4. Kepemimpinan ternyata tidak sekedar berfokus untuk
memerintah dengan otoritas legal formal, namun juga menciptakan suasana yang mampu
membangkitkan motivasi bawahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pemimpin yang
dibutuhkan oleh organisasi adalah pemimpin yang dapat menunjukkan kualitas dirinya.5
Bagi orang Jawa pemimpin yang ideal merupakan perpaduan antara tokoh agama atau
ulama, panglima perang dan raja6. Dengan perpaduan itu diharapkan akan lahir pemimpin yang taat
dalam beragama sekaligus dapat mengatur masalah-masalah kehidupan beragama, memiliki jiwa
pemberani dan pilih tanding sebagai panglima perang sekaligus bijaksana dan adil sebagai raja atau
penguasa.7 Sejarah telah mencatat bahwa setelah Islam masuk ke Nusantara dan sejak akhir abad
ke-15 telah menjadi kekuatan politik yaitu munculnya satu kerajaan Islam pertama Jawa yang
bernama Demak Bintoro, maka muncul konsep kepemimpinan yang bersifat integratif, yaitu:
Sayijdin Panata Gama, Senopati Ing Ngalogo, Khalifatullah Fil-Ardh (Penguasa yang mengatur
agama, Panglima di medan perang dan Wakil Tuhan di bumi).8 Inilah gelar yang diberikan Wali
Songo ketika melantik Raden Patah menjadi Raja Islam pertama di Kerajaan Demak. Betapa arif
bijaksananya Wali Songo memberikan gelar pada penguasa Islam yang tidak serta merta
menggunakan istilah yang umum digunakan para penguasa Islam di Timur Tengah saat itu yaitu
menggunakan sebutan “Khalifah” dan “Amir”.
Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus mempunyai kualitas spiritual, terbebas
dari segala dosa, memiliki kemampuan sesuai dengan realitas dan tidak terjebak pada kenikmatan
dunia. Urgensi kepemimpinan dalam Islam adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan
menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan, yang didasari atas nila-nilai Islam. Usaha yang
paling praktis ialah mencontoh akhlak atau perilaku Rasulullah Muhammad saw dalam memimpin
umat Islam. Selain mendapat julukan Al-Amin karena kejujurannya, Rasul merupakan suri tauladan
yang baik. Rasulullah Muhammad saw bagi orang Islam adalah uswatun hasanah yang harus ditiru
dalam segi perilaku dan perkatannya. Sifat Rasulullah yang dapat menjadi panutan seseorang dalam
menjalankan kepemimpinannya sangat banyak, namun ada 4 sifat dasar yang sesuai untuk dijadikan
suri tauladan yang baik, yaitu shidiq, amanah, tabligh dan fathonah.9
4 Hardi Mulyono, “Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan
Tinggi,” Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol.3 No.1 (2018): 291 5 Marsetio, Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership (Bogor: Univ. Pertahanan, 2018): 61
6 Sri Wintala Achmad, Falsafah Kepemimpinan Jawa, (Yogyakarta: Araska,2013): 24
7 Hardi Mulyono, “Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan
Tinggi” Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3. No. 1 (2018): 294 8 Ahmad Febri Kurniawan “Falsafah Kepemimpinan Pendidikan (Hasta Brata sebagai Basis Kepemimpinan
Pendidikan)” Ri’ayah Vol. 04, No. 02, Juli-Desember (2019): 199 9 Sarjana Sigit Wahyudi, “Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam Dalam Masyarakat Jawa” Sabda Vol. 6 No. 1 April
(2021): 23
3
Terdapat sebuah kaitan antara Islam sebagai suatu rancangan yang menyeluruh untuk
menata kehidupan umat manusia, dengan politik dalam arti kepemimpinan sebagai satu-satunya alat
yang dipakai untuk menjamin ketaatan universal terhadap rancangan tersebut. Konsep ini telah
difahami oleh Nabi Muhammad saw sebagai sebuah cara untuk membangun peradaban Islam dalam
bidang Politik Ketatanegaraan. Hal itu tampak pada keberhasilannya dalam meletakkan landasan
sebuah negara yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam pada masa pemerintahan Islam waktu itu.
Khususnya perkembangan Islam di Jawa dalam hal kepemimpinan yang berkualitas yang memiliki
komitmen kepemimpinan terekam dalam karya sastra Jawa.10
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro merupakan salah satu karya sastra Jawa yang membahas
tentang kepemimpinan Islam-Jawa yang berbasis manajemen organisasi. Kyai Ageng Imam Puro
merupakan seorang ulama Ponorogo yang punya kredibilitas tinggi dan wawasan yang luas,
ditambah lagi dengan konteks sosial politik nusantara waktu itu dan dengan latar belakang dan
sejarah penulisan yang kompleks akan sangat menarik untuk dibahas Manuskrip Kyai Ageng Imam
Puro ini. Jika dilihat dari isinya, Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro ini cukup tebal karena terdapat
82 halaman serta mempunyai keistimewaan yang luar biasa dalam mengulas masalah
kepemimpinan diantaranya pertama, dari sisi sajian redaksi kalimatnya yang kental nuansa sastra.
Kedua, referensi naskah yang autentik. Ketiga, kontekstualisasi dengan kondisi ke-Indonesiaan
khususnya Jawa. Seharusnya pemikiran Kyai Ageng Imam Puro ini masih sangat layak dan penting
untuk menjadi referensi atau acuan bagi orang Jawa ketika mengkaji hal yang berkaitan dengan
permasalahan Kepemimpinan.
Dari berbagai pemaparan dan latar belakang peneliti di atas, peneliti akan mendeskripsikan
dan menguraikan kepemimpinan Jawa-Islam yang berbasis manajemen organisasi dalam Manuskrip
Kyai Ageng Imam Puro. Sehingga, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas,
sebenarnya masyarakat Jawa memiliki warisan leluhur yang adiluhung yang ada dalam karya sastra
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro yang kaya akan nilai teladan, baik secara eksplisit maupun
implisit. Nilai adiluhung ini haruslah terus tetap dijaga serta dibina guna memperkuat penghayatan
dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas hidup, mempertegas jati diri
bangsa, menjadi kebanggan nasional, serta menjadi penggerak dalam mencapai cita-cita bersama.
Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengangkat kembali kepemimpinan Jawa sebagai
sebuah kebudayaan dan kearifan lokal dari konsepsi kepemimpinan yang multivarian. Dengan dasar
inilah penulis mencoba membahas dan memperkenalkan konsep kepemimpinan Islam-Jawa dalam
manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dan Implementasi Kepemimpinan Publik di Indonesia.
10
Ibid., 261
4
B. Rumusan Masalah:
1. Bagaimana konsep kepemimpinan Islam-Jawa dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro?
2. Bagaimana Implementasi Kepemimpinan Publik dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
diantaranya:
1. Untuk menganalisis konsep kepemimpinan Islam-Jawa dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam
Puro.
2. Untuk menganalisis Implementasi Kepemimpinan Publik dalam Manuskrip Kyai Ageng Imam
Puro.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian kepemimpinan yang bersumber
dari naskah-naskah Jawa tradisional abad XVIII yang digambarkan pada Manuskrip Kyai
Ageng Imam Puro sebagai penyeimbang (equilibrium) dan pembanding kultural (counter
culture) dari pada kajian-kajian kepemimpinan modern selama ini.
2. Manfaat Praktis
Bagi pembaca atau masyarakat pada umumnya, penelitian ini setidaknya dapat
memberikan kontribusi ideasional terkait kepemimpinan berbasis literatur lokal (local genus
literature) yang diharapkan dapat dijiwai (internalization) dan dilaksanakan (implementation)
dalam kehidupan sosial. Sedangkan bagi penulis/peneliti khususnya, penelitian ini diharapkan
memberikan proyeksi diskursus atau wacana kontekstual kepemimpinan Jawa yang relevan
dengan pendidikan Islam sebagai latar belakang akademik penulis/peneliti.
E. Kajian Pustaka
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini
diantaranya:
Pertama, Tesis Izzudin Rijal Fahmi tahun 2020 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)
dengan judul “Ajaran Kepemimpinan Jawa (Kajian atas Serat Nitisruti dan Relevansinya dengan
Pendidikan Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi naskah Serat Nitisruti, dan
menganalisis ajaran kepemimpinan Jawa dalam Serat Nitisruti dan relevansinya dengan pendidikan
Islam. Menggunakan metode filologi yang terdiri dari inventarisasi naskah, deskripsi naskah,
suntingan teks, terjemahan teks, dan analisis isi. Teori yang digunakan diantaranya hermeneutika,
semiotika, dan interaksionisme-simbolik. Berdasarkan analisis terhadap Serat Nitisruti disimpulkan
bahwa Serat Nitisruti (niti: kepemimpinan, sikap/perilaku baik; sruti: ilmu, pernyataan), dan ajaran
5
kepemimpinan Jawa dalam Serat Nitisruti meliputi kedudukan yang dipimpin (kawula), kedudukan
pemimpin (gusti), serta relasi pemimpin (gusti) dan yangdipimpin (kawula).
Kedua, Penelitian Ahmad Febri Kurniawan tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga ) dengan judul “Falsafah Kepemimpinan Pendidikan (Hasta Brata sebagai basis
kepemimpinan pendidikan)”. Dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang
digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dalam rangka melihat dan menganalisis kerangka
konseptual falsafah Hasta Brata dan implikasinya terhadap konsep kepemimpinan pendidikan.
Hasta Brata mengajarkan perlunya fleksibilitas kepala sekolah dalam kepemimpinannya. Terkait
dengan kematangan anggota, kepala sekolah harus fleksibel menggunakan gaya suportif, delegatif,
konsultatif atau direktif dalam kepemimpinannya.
Ketiga, Penelitian Sarjana Sigit Wahyudi tahun 2011 (Universitas Diponegoro) dengan judul
“Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam Dalam Masyarakat Jawa”. Penelitian ini membicarakan
tentang sifat pemimpin berdasarkan model kepemimpinan tradisonal Jawa dan Islam. Ada beragam
tipe atau model kepemimpinan dan sifat-sifat ideal pemimpin, dalam model kepemimpinan
tradisional Jawa dan Islam, model kepemimpinan dan sifat-sifat pemimpin itu dipandang lebih
selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan mayoritas menganut Islam.
F. Kerangka Teori
1. Hermeneutika Double Movement
Pengertian secara sederhana bahwa hermeneutika sebagai sebuah kajian tentang
penafsiran atau pemahaman sebuah teks masa lalu sehingga bisa bermakna secara eksistensial
pada saat ini. Inti dari teori yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman terletak pada apa yang
dinamakannya sebagai teori gerak ganda (double movement theory), yakni proses penafsiran
yang ditempuh melalui dua gerakan (langkah), dari situasi sekarang ke masa teks itu ada dan
kembali lagi ke masa kini.11
Dalam gerakan pertama, pemahaman diarahkan pada makna dari
suatu pernyataan teks dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan teks
tersebut merupakan jawabannya. Oleh karena itu kajian mengenai situasi makro yang berkaitan
dengan masyarakat, agama, adat istiadat, bahkan mengenai kehidupan menyeluruh di
masyarakat mesti dilakukan terlebih dahulu. Langkah pertama ini pada dasarnya merupakan
pemahaman terhadap makna teks sebagai suatu keseluruhan, di samping juga memahaminya
dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi yang khusus pula.
Jadi, yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari konteks makro dan mikro di mana teks
pertama kali ditulis.12
11
Ramli Abdul Wahid, MA., Ulumul Qur’an, Ed. Rev,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 81 12
Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, (Chicago & London: The
university of Chicago Press, 1982), 7
6
Gerakan kedua yang dilakukan adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik
tersebut sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari
ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratiolegis yang sering
dinyatakan. Oleh karena itu, langkah pertama, memahami makna dari ayat spesifik,
sesungguhnya telah mengimplikasikan langkah kedua dan membawa kepadanya. Selama proses
ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran teks sebagai suatu keseluruhan (kesatuan)
sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan
yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Dengan ungkapan lain tidak akan ada
kontradiksi di dalamnya tetapi justru koherensi secara keseluruhan.13
Sementara gerakan
pertama terjadi dari hal-hal spesifik dalam teks ke penggalian dan sistematisasi prinsip umum,
nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya; gerakan kedua dilakukan dari pandangan umum ini
ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya, ajaran-
ajaran yang bersifat umum tersebut harus dijelmakan dalam konteks sosio-historis yang
kongkrit pada saat sekarang.14
Oleh karena itu diperlukan analisis yang cermat atas situasi sekarang dan mengubah
kondisi sekarang sejauh yang dibutuhkan, kemudian menentukan prioritas baru untuk dapat
mengimplementasikan nilai-nilai teks secara baru pula. Tugas gerakan pertama merupakan
kerja para ahli sejarah, sementara tugas gerakan kedua merupakan kerja para ahli etika yang
mesti didukung oleh para ahli ilmu sosial. Jika kita berhasil mencapai kedua gerakan dari gerak
ganda tersebut dengan benar, maka perintah-perintah teks akan menjadi hidup dan efektif
kembali pada saat ini.
2. Interaksi Simbolik
Interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah
laku manusia melalui analisis makna.15
Interaksionisme simbolik merupakan salah satu model
penelitian budaya yang berusaha mengungkap realitas perilaku manusia. Perspektif interaksi
simbolik berusaha memahami budaya lewat perilaku manusia yang terpantul dalam
komunikasi. Interaksi simbolik lebih menekankan pada makna interaksi budaya sebuah
komunitas. Makna esensial akan tercermin melalui komunikasi budaya antar warga setempat.
13
Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 88. Lihat pula Erle H. Waugh dan
Frederick M Denny (eds.), The Shaping of An American Islamic Discourse; A Memorial to Fazlur Rahman, (Georgia:
Scholar Press Atlanta, 1998), 38 14
Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1946), 32-34 15
George Ritzer dan Douglas J. Goddman, Teori Sosiologi Modern, Terj. Alimandan, (Jakarta: Prenada media, 2005),
43
7
Pada saat berkomunikasi manusia banyak menampilkan simbol-simbol yang memiliki banyak
makna, sehingga perlu dilakukan pengamatan untuk dapat menemukan maknanya.16
Kajian Interaksionisme simbolik adalah salah satu kajian dari sosiolinguistik. Dan
dalam perspektif sosiolinguistik bahwa praksis bahasa seseorang atau sekelompok orang, yang
mencakup dialek, register, jargon dan sebagainya, dibentuk oleh:17
a. Posisi dalam struktur sosial seperti nativitas, bahasa ibu, tempat tinggal, pendidikan,
pekerjaan, kelas sosial, dan jenis kelamin.
b. Formalitas dan informalitas percakapan dan audiensnya.
c. Proses produksi linguistiknya, yang pada akhirnya menentukan keluaran interaksionalnya.
Peneliti ini ingin menguraikan interaksi antara kepemimpinan Islam dan kepemimpinan
Jawa dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro sebagai ungkapan pesan baik verbal maupun
perilaku non verbal, dengan bertujuan mencoba memaknai simbol atau lambang tersebut
melalui kesepakatan bersama, yang diberlakukan dalam wilayah atau kelompok komunitas
masyarakat tertentu.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis, karena pada penelitian
ini penulis menggali pemikiran seorang tokoh yang dituangkan dalam karyanya. Pada
penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni
penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Hal ini dimaksudnya
untuk menggali teori-teori serta konsep-konsep terdahulu yang telah di cetuskan serta telah
dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya serta untuk memperluas bahan yang dimiliki
dalam membahas materi yang ingin diteliti dan juga untuk menghindari plagiasi atau duplikasi
dalam penelitian yang akan dilakukan18
.
2. Data
Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya. Data ini adalah berupa Manuskrip Kyai
Ageng Imam Puro sebagai sumber analisis penelitian.
3. Sumber Data
a. Sumber primer yang peneliti gunakan adalah kitab manuskrip Kyai Ageng Imam Puro.
16
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 55 17
Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa Dan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 56 18
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011), 243
8
b. Sumber sekundernya dalam penulisan ini adalah adalah informasi yang berasal dari orang
lain yang ada kaitannya dengan pembahasan, yakni buku-buku bacaan, artikel dan jurnal.
Diantaranya sebagai berikut:
1) Buku :
a) Sri Wintala Achmad. Falsafah Kepemimpinan Jawa, (Yogyakarta: Araska,2013)
b) Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal
Itu?, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
c) Sutarto Wijono, Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi, (Jakarta: Prenada
Media, 2018)
d) Manahan P. Tampubolon, Change Management, (Jakarta: Mitra Wacana, 2020)
2) Jurnal :
a) Sarjana Sigit Wahyudi, “Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam Dalam Masyarakat
Jawa” Sabda Vol. 6 No. 1 April (2021)
b) Hardi Mulyono, “Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan
Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi,” Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora
Vol.3 No.1 (2018): 291
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu
studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.19
Kegiatan
penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan
tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi,
majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.20
Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun
kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha
Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui
tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data
ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relavan terhadap masalah yang
diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang konsep
kepemimpinan Islam-Jawa dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dan Implementasi
Kepemimpinan Publik di Indonesia.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data
19
Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001, 91 20
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, ArRuzz Media, Jogjakarta, cet
III, 2016, 208
9
yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa tulisan-tulisan, buku, artikel-artikel yang relevan dengan tema
yang diteliti yaitu dengan membaca dan mencari data yang berkaitan dengan konsep
kepemimpinan Islam-Jawa dan kepemimpinan publik. Serta membaca dan mencari data yang
berkaitan dengan teori double movement Fazlur Rahman.
Penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini melakukan beberapa tahap,
yaitu mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kemudian memilih
bahan pustaka yang dijadikan sumber primerdan sekunder, membaca bahan pustaka yang
telah dipilih kemudian mencatat isi bahan yang berhubungan dengan konsep kepemimpinan
Islam-Jawa dan kepemimpinan publik.
5. Uji Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik
pemeriksaan didasarkan atas sujumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan,
yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan
(dependability), dan kepastian (confirmability).21
Dari beberapa uji tersebut , dalam penelitian
ini telah diutamakan adalah uji kredebilitas semata yang dilakukan dengan cara triangulasi
karena triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran untuk tentang beberapa
fenomena, tetapi ditemukan, teknik triangulasijuga lebih mengutamakan efektifitas proses dan
hasil yang diinginkan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
a) Triangulasi dengan sumber
b) Triangulasi dengan metode
c) Triangulasi penyidik
d) Triangulasi teori
6. Analisis Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan tehnik
berikut ini untuk mengolah data:
a) Reduksi data (data reduction)
Proses reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya, dalam hal ini
memilih hal-hal yang berhubungan dengan aspek konsep kepemimpinan Islam-Jawa dan
kepemimpinan publik dan teori double movement sehingga dapat memberikan gambaran yang
21
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, 324
10
lebih jelas dan mempermudah dalam proses pengumpulan data.22
Data yang diperoleh
kemudian diolah melalui tahapan memahami, mengamati setiap kata dan menuliskan berbagai
informasi yang berhubungan dengan reinterpretasi konsep konsep kepemimpinan Islam-Jawa
dan kepemimpinan publik yang sedang diteliti.
b) Penyajian data (data display)
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data (data display).
Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama
lain. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat danbagan. Hal ini dilakukan
untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan
menghasilkan suatu kesimpulan.23 Dalam hal ini, penulis mulai menyajikan data dalam
bentuk teks yang bersifat diskriptif mulai dari sejarah ditulisnya manuskrip dan kondisi sosial
orang Jawa pada zaman itu, dan seterusnya.
c) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi data (conclusion drawing/verification)
Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami
kembali data-data hasil penelitian sehingga diharapkan kesimpulan yang diperoleh dapat
menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal.
H. Sistematika Penelitian
Penyusunan penulisan pada penelitian ini dirancang melalui sistematika sebagai berikut:
1. Bab I (Pendahuluan) berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian serta
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta
sistematika penelitian.
2. Bab II (Kajian Pustaka) Konsep dasar kepemimpinan yang terbagi menjadi tiga sub bab.
Pertama, kepemimpinan publik. Kedua, kepemimpinan Islam. Ketiga, kepemimpinan Jawa.
3. Bab III (Biografi Tokoh) Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro yang yang terbagi menjadi dua
sub bab. Pertama, profil dan biografi Kyai Ageng Imam Puro. Kedua, identifikasi naskah,
meliputi : deskripsi naskah, suntingan naskah dan terjemah naskah.
4. Bab IV (Pembahasan I) konsep kepemimpinan Islam-Jawa Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
5. Bab V (Pembahasan II) Implementasi Kepemimpinan Publik di Indonesia dalam Manuskrip
Kyai Ageng Imam Puro.
6. Bab VI (Penutup) menguraikan kesimpulan serta saran kepada peneliti.
22
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011), 243 23
Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, (Chicago & London: The
university of Chicago Press, 1982), 7
11
BAB II
KONSEP DASAR KEPEMIMPINAN
A. Kepemimpinan Publik
1. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi. Menurut Stogdi dalam
Dr. M. Sobry Sutikno menyatakan bahwa, Kepemimpinan sebagai konsep manajemen dapat
dirumuskan dalam berbagai macam definisi tergantung dari mana titik tolak pemikirannya.1
Beberapa pengertian kepemimpinan menurut pendapat para ahli, menurut Achmad Sanusi dan M.
Sobry Sutikno adalah berikut ini: 2
a. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur
untuk mencapai tujuan bersama. (Rauch & Behling).
b. Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan
penuh kemauan untuk tujuan kelompok. (George P. Terry).
c. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai
tujuan umum. ( H. Koontz dan C. Donnell).
d. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna
mencapai tujuan tertentu yang diinginkan” (Ordway Tead).
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan
untuk mempengaruhi dan menggerakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam
organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat seperti
yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya.
2. Teori-Teori Kepemimpinan
Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seorang menjadi pemimpin, atau bagaimana
timbulnya seorang pemimpin. Beberapa teori kepemimpinan diantaranya sebagai berikut: 3
a. Teori Sifat
Teori ini penekanannya lebih pada sifat-sifat umum yang dimiliki pemimpin, yaitu sifat-
sifat yang dibawa sejak lahir. Menurut teori sifat, hanya individu yang memiliki sifat-sifat
tertentulah yang bisa menjadi pemimpin. Teori ini menegaskan ide bahwa beberapa individu
dilahirkan memiliki sifat-sifat tertentu yang secara alamiah menjadikan mereka seorang
pemimpin.
1 M. Sobry Sutikno, Pemimpin dan Kepemimpinan (Lombok: Holistica, 2014), 15
2 Hamzah Zakub, Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan, ( Bandung: CV Diponegoro), 125
3 Nasharuddin Baidan& Erwati Aziz, Etika islam dalam Berbisnis ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 127
12
Menurut Stogdill dalam Sutikno, sifat-sifat tertentu efektif di dalam situasi tertentu, dan
ada pula sifat – sifat tertentu yang berkembang akibat pengaruh situasi organisasi. Sebagai
contoh, sifat kreativitas akan berkembang jika seorang pemimpin berada di dalam organisasi
yang flexible dan mendorong kebebasan berekspresi, dibandingkan di dalam organisasi yang
birokratis. Menurut Darf dalam Sutikno, menjelaskan tiga sifat penting yang harus dimiliki oleh
seorang pemimpin, yaitu kepercayaan diri, kejujuran, dan integritas, serta motivasi. 4
b. Teori Perilaku
Teori ini lebih terfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin dari pada
memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang pemimpin. Dasar pemikiran teori ini
adalah kepemimpinan merupakan perilaku seseorang ketika melakukan kegiatan pengarahan
suatu kelompok kearah pencapaian tujuan.
c. Teori Situasional
Teori ini mengatakan bahwa pembawaan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah
berbeda-beda, tergantung dari situasi yang sedang dihadapi. Hersey dan Blanchard dalam
Sutikno, terfokus pada karakterisitik kematangan bawahan sebagai kunci pokok situasi yang
menentukan keefektifan perilaku seorang pemimpin. Menurut mereka, bawahan memiliki
tingkat kesiapan dan kematangan yang berbeda-beda sehingga pemimpin harus mampu
menyesuaikan gaya kepemimpinannya, agar sesuai dengan situasi kesiapan dan kematangan
bawahan. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu adalah: 5
1) Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas
2) Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan
3) Norma yang dianut kelompok
4) Ancaman dari luar organisasi
5) Tingkat stress
6) Iklim yang terdapat dalam organisasi Menurut Fread Fiedler dalam Sutikno,
Kepemimpinan yang berhasil bergantung kepada penerapan gaya kepemimpinan terhadap
situasi tertentu. Sehingga suatu gaya kepemimpinan akan efektif apabila gaya
kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat.
d. Teori Jalan-Tujuan
Menurut teori ini, nilai strategis dan keefektifan seorang pemimpin didasarkan pada
kemampuannya dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi anggotanya dengan penerapan
hadiah. Tugas pemimpin menurut teori ini adalah bagaimana bawahan bisa mendapatkan
4 Vietzal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta; PT Raja
Grafindo Persada, 2013), 21 5 Susilo Martoyo, Manajemen Sumberdaya Manusia ( Yogyakarta: BPFE, 2000), 184-186
13
hadiah atas kinerjanya, dan bagaimana seorang pemimpin menjelaskan dan mempermudah
jalan menuju hadiah tersebut. Pemimpin berusaha memperjelas jalur menuju tujuan yang
diinginkan oleh organisasi sehingga bawahan tahu ke mana harus mengerahkan tenaganya
untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, pemimpin juga memberikan hadiah yang jelas
bagi prestasi bawahan yang telah memenuhi tujuan organisasi sehinggan bawahan termotivasi.
e. Teori Kelebihan
Teori ini beranggapan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki
kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin mencakup 3 hal yaitu: 6
1) Kelebihan rasio, ialah kelebihan menggunakan pikiran, kelebihan dalam pengetahuan
tentang hakikat tujuan dari organisasi, dan kelebihan dalam memiliki pengetahuan
tentang cara-cara menggerakkan organisasi, dan pengambilan keputusan yang cepat dan
tepat.
2) Kelebihan Rohaniah, artinya seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keluhuran
budi pekertinya kepada bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai moral yang
tinggi karena pada dasarnya pemimpin merupakan panutan para pengikutnya. Segala
tindakan, perbuatan, sikap dan ucapan hendaknya menjadi suri teladan bagi para
pengikutnya.
3) Kelebihan Badaniah, seorang pemimpin hendaknya memiliki kesehatan badaniah yang
lebih dari para pengikutnya sehingga memungkinkannya untuk bertindak dengan cepat.
f. Teori Kharismatik
Menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena mempunyai kharisma
(pengaruh) yang sangat besar. Kharisma diperoleh dari kekuatan yang luar biasa. Pemimpin
yang bertipe kharismatik biasanya memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang sangat
besar. Pengaruh yang luar biasa ini dapat dilihat dari pengorbanan yang diberikan oleh para
pengikut untuk pribadi sang pemimpin, sampai-sampai mereka rela untuk menebus nyawanya
untuk sang pemimpin.7 Konsep kepemimpinan yang kharismatik ini banyak bersumber dari
ajaran agama dan sejara Yunani Kuno. Namun secara konseptual kepemimpinan kharismatik
ini dalam pandangan ilmiah dipelopori oleh Robert House, yang meneliti pemimpin politik dan
religius di dunia.
6 Usman Effendi, Asas Manajemen (Jakarta: PT Raja Grafindo,2011), 188-189
7 Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009), 101-102
14
3. Tipe-Tipe Kepemimpinan
Dalam upaya menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan
yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang pemimpin memiliki beberapa tipe (bentuk)
kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya
kepemimpinan. Berikut adalah tipe-tipe kepemimpinan yang luas dan dikenal dan diakui
keberadaannya: 8
a. Tipe Otokratik
Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya
(pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang
lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian
karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Jadi, seorang
pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang :
1) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi
2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi
3) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata
4) Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat
5) Terlalu tergantung kepada kekuasan formilnya
6) Dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung
unsur paksaan dan bersifat menghukum
b. Tipe Kendali Bebas (Laissez-Faire)
Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam
tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar
diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin kendali bebas cenderung memilih peran yang
pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Sifat kepemimpinan pada
tipe kendali bebas seolah-olah tidak tampak. Kepemimpinannya dijalankan dengan
memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan
melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik perseorangan
maupun kelompok-kelompok kecil. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa
dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya
akan cepat berhasil. 9
8 Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009), 106-107 9 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: PT Grafindo persada,2003), 10-11
15
c. Tipe Demokratik
Yang dimaksud dengan tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis, dan
bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan di mana
pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan
bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Untuk mencapai
keefektifan organisasi, penerapan beberapa tipe kepemimpinan di atas perlu disesuaikan
dengan tuntutan keadaan. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan situasional. Untuk dapat
mengembangkan tipe kepemimpinan situasional ini, seseorang perlu memiliki tiga kemampuan
khusus yakni : 10
1) Kemampuan analitis, kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi
bawahan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan untuk fleksibel, kemampuan untuk
menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi
2) Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang
perubahan gaya kepemimpinan yang diterapkan.
B. Kepemimpinan Islam
1. Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.
Dalam sejarah perkembangan kepemimpinan di dunia Islam, model kepemimpinan pastinya
sangat dipengaruhi oleh tokoh sentral pada masa tersebut. Zaman Rasulullah Saw, tokoh utama
kepemimpinan tentunya adalah Rasulullah Saw. Di masa kepemimpinan beliau, bisa dikatakan
bahwa model kepemimpinan yang beliau jalankan adalah model kepemimpinan situasional. Yakni
model kepemimpinan yang memadukan antara model kepemimpinan otokratis, permisif, dan
partisipatif secara konsisten.11
Sebagaimana diketahui, model kepemimpinan situasional adalah perpaduan antara model
kepemimpinan dimana seorang pemimpin dapat menggunakan model kepemimpinannya sesuai
dengan situasi dan kondisi yang mendukung, yakni kapan dia harus menentukan sendiri kebijakan
dan menugaskannya kepada staf tanpa berkonsultasi dengan mereka, mengarahkan secara rinci dan
harus dilaksanakan tanpa pertanyaan, kapan dia harus memberi kepercayaan penuh kepada
bawahannya dengan prinsip umum bahwa pada prinsipnya semua manusia terlahir
bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untukmelaksanakan kewajibannya, yang terakhir
kapan dia harus melibatkan stafnya dalam memutuskan suatu perencanaan.
Dalam masa keemasan pertama, yakni di masa kenabian, Rasulullah sangat sering
mempraktekkan kepemimpinan situasional ini. Diantara contoh yang dapat disuguhkan adalah
10
Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati, dan Agung Ayu Sriathi, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009), 90 11
Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, Aplikasi Syariat Islam (Jakarta : Darul Fallah, 2002), 21
16
ketika beliau mengirimkan Mush’ab bin Umair untuk menjadi duta pertama Islam ke Madinah yang
saat itu masih bernama Yatsrib. Misi ini sebenarnya merupakan pekerjaan berat, dimana objek
pendidikan adalah masyarakat Yatsrib yang hampir 100% adalah penganut agama nenek moyang.12
Nabi Muhammad Saw memberi kepercayaan begitu saja kepada Mush’ab bin Umair karena beliau
telah mengetahui akan kapasitas Mush’ab. Mush’ab saat masih di Makkah terkenal sebagai ahli
negosiasi yang sangat diakui kehebatannya. Benar terbukti Mush’ab mampu membuat masyarakat
Yatsrib secara berangsur-angsur melakukan bai’at ke Mekkah menemui Nabi Muhammad Saw.
Puncaknya adalah hijrahnya Rasulullah Saw ke Yatsrib dengan disambut secara gegap gempita oleh
seluruh masyarakat Arab asli Yatsrib dengan nasyid yang terkenal thola’al badru ‘alaina. Model
kepemimpinan seperti ini adalah yang bisa disebut dengan model kepemimpinan permisif.
Contoh lainnya adalah ketika Rasulullah Saw hendak menentukan bagaimana cara
mengundang manusia untuk melaksanakan shalat, maka dilakukanlah musyawarah bersama para
shahabat dan akhirnya muncullah lafaz adzan yang ternyata merupakan hasil mimpi salah seorang
shahabat. Dalam kasus model kepemimpinan seperti ini Rasulullah Saw senantiasa jalankan dalam
banyak hal termasuk musyawarah menentukan strategi peperangan. Model kepemimpinan seperti
ini adalah yang bisa disebut dengan model kepemimpinan partisipatif. Sementara contoh model
kepemimpinan otokratis adalah ketika Rasulullah Saw memerintahkan kepada shahabat Ali Ra
untuk tidur di kamar Rasulullah Saw tanpa memberi alasan sedikitpun kepada Ali Ra dan tanpa
memberi peluang sedikit saja kepada Ali untuk bertanya.
Seluruh model kepemimpinan ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw selaku tokoh
sentral pendidikan dalam menjalankan model kepemimpinannya yang sangat khas dan kaya. Pada
masa kepemimpinan Rasul memang selalu dituntun oleh wahyu, jika tidak ada wahyu maka rasul
berijtihad baik melalui musyawarah maupun inisiatif beliau sendiri. Jika keputusan itu benar, Allah
membiarkannya dalam arti tidak ada teguran wahyu, tapi jika ketetapan Rasul atau ijtihadnya itu
tidak tepat maka turunlah wahyu. Dari dasar itu, maka segala keputusan yang diambil masa
kepemimpinan Rasul selalu benar.
2. Kriteria Pemimpin Islam
Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai
empat sifat utama, yaitu:13
a. Shidiq (Jujur)
Kejujuran adalah lawan dari dusta dan memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana
dengan fakta. Di antaranya yaitu kata rajulun shaduq (sangat jujur), yang lebih mendalam
maknanya daripada shadiq (jujur). Al-mushaddiq yakni orang yang membenarkan setiap
12
Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik ( Jakarta: Gema Insani, 2003), 120 13
Harahap Sofyan S. Etika Bisnis Dalam Perspektif islam, Jakarta; Salemba Empat, 2011, h.76
17
ucapanmu, sedang ash-shiddiq ialah orang yang terus menerus membenarkan ucapan orang,
dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Kejujuran
merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada
pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi.
Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para
pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh
dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya.14
Seorang pemimpin yang sidiq atau bahasa
lainnya honest akan mudah diterima di hati masyarakat, sebaliknya pemimpin yang tidak jujur
atau khianat akan dibenci oleh rakyatnya. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari perkataan
dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkataannya, dan
perkatannya merupakan cerminan dari hatinya. Nabi Saw disifati dengan ash-shadiqul amin
(jujur dan terpercaya), dan sifat ini telah diketahui oleh orang Quraisy sebelum beliau diutus
menjadi rasul.
b. Amanah (terpercaya)
Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan
memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah
diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan maskarakat berupa penyerahan segala macam
urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Amanah
erat kaitanya dengan tanggung jawab. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang
bertangggung jawab. Dalam perspektif Islam pemimpin bukanlah raja yang harus selalu
dilayani dan diikuti segala macam keinginannya, akan tetapi pemimpin adalah khadim.
Sebagaimana pepatah Arab mengatakan “sayyidulqaumi khodimuhum”, pemimpin sebuah
masyarakat adalah pelayan mereka. Sebagai seorang pembantu, pemimpin harus merelakan
waktu. Tenaga dan pikiran untuk melayani rakyatnya.
Pemimpin dituntut untuk melepaskan sifat individualis yang hanya mementingkan diri
sendiri. Ketika menjadi pemimpin maka dia adalah kaki-tangan rakyat yang senantiasa harus
melakukan segala macam pekerjaan untuk kemakmuran dan keamanan rakyatnya. Dalam buku
The Indispensable Quality of Leader, John C. Maxwell menekankan bahwa tanggung jawab
bukan sekedar melaksanakan tugas, namun pemimpin yang bertanggung jawab harus
melaksanakan tugas dengan lebih, berorienatsi kepada ketuntasan dan kesempurnaan. “Kualitas
tertinggi dariseseorang yang bertangging jawab adalah kemampuannya untuk
menyelesaikan”.15
14
Tasmara Toto, Spiritual Centered Leadership (Jakarta : Erlangga, 2005), 163 15
Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yokyakarta : Gajah Mada Unuversiuty Press, 2001), 17
18
c. Tabligh (Komunikatif)
Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh
pemimpi sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan
dipindah-pindah sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan
rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu komunikasi
merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. Salah satu ciri
kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran
meskipun konsekuensinya berat. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, “kul al-haq walau
kaana murran”, katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya.
Tabligh juga dapat diartikan sebagai akuntabel, atau terbuka untuk dinilai. Akuntabilitas
berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dala kaitannya dengan cara
mempertanggungkawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Sehingga, akuntabilitas merupakan
bagian melekat dari kredibilitas. Bertambah baik dan benar akuntabilitas yang miliki,
bertambah besar tabungan kredibilitas sebagai hasil dari setoran kepercayaan orang-orang.16
d. Fathanah (Cerdas)
Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehinga
memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan
segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah
frustasi menghadapai problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi.
Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu
tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu. Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang
dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar
untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan
ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akanmemiliki derajat tinggi di
mata manusia dan juga pencipta.
3. Ciri Kepemimpinan Islam
Kepemimpinan menurut Rivai juga memiliki beberapa ciri penting yang menggambarkan
kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:17
a. Setia: pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah Swt.
b. Tujuan: pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan
kelompok tetapi juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang lebih luas.
c. Berpegang pada syariat dan akhlak Islam: pemimpin terikat dengan peraturan Islam, boleh
menjadi pemimpin selama ia berpegang pada perintah syariat. Waktu mengendalikan
16
2Tasmara Toto, Spiritual Centered Leadership (Jakarta : Erlangga, 2005), 19 17
Veithzal Rivai, Kiat Kepemimpinan dalam Abat-21 (Jakarta : Murai Kencana, 2004), 72
19
urusannya ia harus patuh kepada adab-adab Islam, khususnya ketika berurusan dengan
golongan oposisi atau orang-orang yang tak sepaham.
d. Pengembang Amanah: menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Swt yang disertai
oleh tanggung jawab yang besar. Qur’an memerintahkan pemimpin melaksanakan
tugasnya untuk Allah Swt dan menunjukkan sikap baik kepada pengikutnya.
e. Tidak sombong: menyadari bahwa diri ini adalah kecil, karena yang besar hanya Allah
Swt, sehingga allahlah yang boleh sombong. Sehingga kerendahan hati dalam memimpin
merupakan salah satu ciri kepemimpinan yang patut dikembangkan.
f. Disiplin, konsisten dan konsekuen: sebagai perwujudan seorang pemimpin yang
profesional yang akan memegang teguh janji, ucapan dan perbuatan yang dilakukan,
karena ia menyadari bahwa Allah Swt mengetahui semua yang ia lakukan bagaimanapun ia
berusaha menyemunyikannya.
Sedangkan menurut Rahman menyatakan, bahwa kepemimpinan Islami, menurutnya, adalah
upaya mengungkap kepribadian Rasulullah Muhammad Saw dalam menjalankan kepemimpinan.
Berdasarkan temuannya, ada beberapa nilai yang menjadikan kepemimpinan Muhammad Saw
sukses, yaitu:18
a. Mutu kepemimpinan
b. Keberanian dan ketegasan
c. Pengendalian diri
d. Kesabaran dan daya tahan
e. Keadilan dan persamaan
f. Kepribadian dan
g. Kebenaran dan kemuliaan tujuan.
4. Azaz-azaz Kepemimpinan Islam
Adapun azas pemimpin dalam Islam, seperti dikemukakan Kamrani Buseri seperti berikut:19
a. Power sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi kekuasaan.
Jadi setiap pemimpin mesti memiliki dua amanah yakni amanah dari
organisasi/lembaga sekaligus amanah dari Tuhannya. Kesadaran spiritualitas ini memberikan
corak kepemimpinan yang sangat berketuhanan dan manusiawi, dia akan membawa
organisasinya ke arah visi ketuhanan dan kemanusiaan, bukan ke arah keserakahan.
18
Rahman, Afzalur, Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 62-77 19
Veithzal Rival Zainal, Subardjo Joyo Sumarto Dkk, Islamic Manajemen, ( Yogyakarta: BPEE, 2013), 296
20
b. Wewenang (authority)
Kewenangan adalah batasan gerak seorang pemimpin sesuai dengan apa yang telah
diberikan oleh pemberinya. Dalam pandangan Islam, wewenang juga dua lapis, yakni
wewenang yang diperoleh sejalan dengan ruang lingkup tingkatan tugas dan tanggung jawab
pemimpin, serta wewenang yang diberikan oleh Tuhan sebagai khalifah-Nya, yakni memiliki
kewenangan atas bumi dan segala isinya, dengan tugas memakmurkan bumi ini. Kesadaran
spiritual adanya kewenangan yang berlapis ini akan menumbuhkan pertanggung jawaban atas
jalannya wewenang yang diterimanya, bahkan akan mempertanggung jawabkan di hadapan
Yang Maha Kuasa kelak. Bilamana seorangpemimpin sudah memiliki power, wewenang dan
amanah, maka dia akan memiliki wibawa atau pengaruh.
c. Keimanan
Iman yang akan membalut power, authority dan amanah tersebut sehingga
kepemimpinan akan dibangun atas dasar bangunan yang komprehensip, kuat dan berorientasi
jauh ke depan tidak sekedar melihat manajemen hanya diorientasikan kepada masalah
mondial (duniawi) semata. Seorang pemimpin yang kuat imannya, dia memahami bahwa
kemampuan memimpin yang dia miliki adalah pemberian Tuhannya. Dia menyadari punya
kekurangan, dan di saat itu dia juga mudah bertawakkal kepada Tuhannya. Sehingga
keberhasilan dan kegagalan baginya akan memiliki makna yang sama, karena keduanya
diyakini sebagai anugerah sekaligus pilihan Tuhannya. Disini pentingnya zero power.
d. Ketakwaan
Takwa sebagai azas kepemimpinan bukan dalam arti yang sempit, yakni takwa berarti
berhati-hati dan teliti. Oleh sebab itu dalam surah al-Hasyr : 18 mengenai perencanaan, Allah
Swt memulai menyeru dengan seruan ”Hai orang-orang yang beriman bertakwalah”, baru
dilanjutkan dengan perintah mengamati kondisi kekinian yang digunakan untuk menyusun
rencana ke depan. Setelah itu ditutup dengan seruan “bertakwalah” kembali. Ini menunjukkan
perencanaan dan implementasi rencana harus dengan kehati-hatian dan ketelitian dalam
mengumpulkan data, pula dalam mengimplementasikannya.
e. Musyawarah
Sebagaimana diterangkan dalam surah as-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159.
Musyawarah penting karena kepemimpinan berkaitan dengan banyak orang. Melalui
musyawarah akan terbangun tradisi keterbukaan, persamaan dan persaudaraan. Perencanaan,
organisasi, pengarahan dan pengawasan selalu saja terkait dengan sejumlah orang, maka
keterbukaan, persamaan dan persaudaraan akan memback up lancarnya proses manajemen
tersebut. Sebuah visi dan misi organisasi, akan semakin baik bilamana dibangun atas dasar
21
musyawarah, akan semakin sempurna dan akan memperoleh dukungan luas, sense of
belonging and sense of responsibility karena masyawarah sebagai bagian dari sosialisasi.
C. Kepemimpinan Jawa
1. Karakteristik Jawa
Wilayah Jawa, atau tana (tanah) Jawa merupakan bagian terbesar dari wilayah yang disebut
oleh para ahli geografi sebagai Kepulauan Sunda. Kepulauan ini acap kali disebut sebagai bagian
dari Kepulauan Malaya yang membentuk gugusan Kepulauan Oriental, yang kemudian disebut
sebagai Kepulauan Asiatik. Terkait nama Jawa, dalam arti terkait asal mula penyebutan nama
sebagai wilayah Jawa, memang tidak ada kepastian. Namun beredar cerita tentang penemuan
bijibijian baru oleh para pendatang India yang diberi nama jawawut. Ada juga yang menyebut
wilayah ini dengan Nusa Hara-hara, atau Nusa Kendang, yang mempunyai makna masih liar atau
yang bertepian dengan perbukitan.20
Asal mula penduduk di wilayah Jawa, disebut-sebut berasal dari nenek moyang yang sama
yakni dari pulau-pulau di timur semenanjung Asia yang merupakan wilayah pertamakali ditempati
manusia. Di kawasan Asia Timur terdapat suatu bangsa yang besar, bangsa Cina, bangsa Jepang
dan beberapa suku bangsa lain yang mendiami Semenanjung India di luar Gangga, dan juga di
pulau-pulau selatan dan timurnya, sampai New Guinea. Ditemukan kemiripan ciri-ciri yang terdapat
pada masyarakat Jawa dengan ciri-ciri bangsa yang disebut di atas. Begitu juga adanya kemiripan
dengan bangsa Birma dan Siam. Berdasar kemiripan ini, baik secara fisik, tingkah laku ataupun adat
istiadat, memperkuat dugaan bahwa penghuni pulau Jawa berasal dari pulau-pulau di wilayah antara
Cina dan Siam. Terkait migrasi dan penyebabnya, memang tidak diketahui secara pasti apa yang
melatarbelakanginya.21
Waktu terus berlanjut, hingga bangsa asing berkunjung ke wilayah Jawa yang
mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Raffles, seorang Inggris, mantan Letnan-Gubernur pulau
Jawa yang memerintah pada tahun 1811-1816 merekam hal itu. Ia menggambarkan kedatangan
Portugis, Belanda, hingga Inggris di Pulau Jawa. Raffles mencatat, Portugis pertama kali melakukan
perjalanan ke kepulaun paling Timur pada tahun 1510, saat Alphonzo de Albuquerqe mendatangi
Sumatera. Lalu Albuquerqe menyuruh Antonio de Abrew ke wilayah Jawa dan Maluku untuk
berdagang. Kekuasaan Portugis terus berlanjut hingga kisaran tahun 1959, ketika Belanda
melakukan pelayaran pertama kali di bawah kendali Houtman. Pada kurun waktu ini Portugis
menyerang Raja Bantam (yang kini dikenal sebagai daerah Banten), bertepatan Belanda yang
20
Berliana Kartakusumah, Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer, (Jakarta: PT Mizan Publika,
2006), 7 21
Suyami, Konsep Kepemimpinan Jawa Dalam Ajaran Sastra Cetha Dan Astha Brata, (Yogyakarta: Kepel Press,
2008), 11-14
22
berlayar dengan tujuan Bantam, langsung menawarkan bantuan, dan sebagai balasan atas jasa
bantuannya pihak Belanda mendapat hak untuk membangun pabrik di daerah Bantam.22
Waktu berlanjut, Badan Dagang milik Inggris menyusul. Di bawah pimpinan Ratu Elizabeth
tahun 1601 Inggis menuju Sumatera dan kemudian pergi ke Bantam. Belanda yang untuk sekian
tahun menempati Bantam akhirnya pada tahun 1610, Bolt, Gubernur Jendral Belanda pertama
menginisiasi perpindahan dari Bantam ke Batavia. Pada tahun 1683 pihak Inggris juga turut pindah
dari Bantam setelah mengalahkan pihak Belanda. Hingga akhirnya pada 11 September tahun 1811,
pemerintah Inggis semakin berkuasa atas wilayah Jawa dengan proklamasi yang ditandatangani
oleh Earl Minto. Namun pada 13 Agustus 1814, sebuah konvensi dibuat agar Inggris menyerahkan
kembali kepada Belanda seluruh kekuasaan atas Hindia Timur. Akhirnya pada 19 Agustus tahun
1816 bendera Belanda kembali berkibar di Batavia.
Terkait agama yang dianut oleh masyarakat Jawa, sebelum kedatangan agama Islam yang
menjadi keyakinan terbesar di kalangan masyarakat Jawa kekinian, masyarakat Jawa menganut
agama Hindu. Dalam catatan sejarah dan tradisi umum di daerah, kerajaan Hindu Majapahit
sekitaran tahun 1475 M yang berdiri dan berkuasa di tanah Jawa harus tergeser sebab datangnya
Islam. Pengaruh Islam juga dirasakan oleh Portugis ketika ia pertamakali berkunjung ke Bantam.
Portugis menemukan raja Hindu di Bantam yang kehilangan hak atas propinsinya sebab keberadaan
raja Islam yang berkuasa. Meskipun Islam sudah menjadi agama masyarakat Jawa, namun tak
semua elemen dari kalangan masyarakat Jawa yang masih enggan meninggalkan kebiasaannya dan
memercayai institusi nenek moyang mereka. Secara dzahirnya masyarakat Jawa sudah tidak pergi
ke candi, namun mereka masih menunjukkan perhatian yang tinggi pada hukum, adatistiadat dan
kebiasaan setempat yang telah ada sebelum datangnya Islam.23
2. Kepemimpinan Politik Jawa
Sebagai sebuah komunitas masyarakat yang mempunyai sejarah panjang dalam
peradabannya, banyak nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Jawa. Franz Magnis
Suseno menuliskan bahwa ada 4 lingkaran dalam pandangan dunia masyarakat Jawa. Lingkaran
pertama adalah sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai sebuah kesatuan kesadaran antara
manusia, alam dan dunia adikodrati. Lingkaran kedua adalah penghayatan kekuasaan politik
sebagai perpanjangan tangan kekuatan adikodrati. Lingkaran ketiga adalah pengalaman mistis-
batiniah manusia Jawa dalam memahami eksistensi dirinya sebagai bagian dari alam. Lingkaran
keempat adalah penentuan semua lingkaran di atas sebagai bagian dari takdir kehidupannya.24
22
Dani Nur Rahman, “Peran Kepemimpinan Jawa” Diponegoro Journal Of Management, Vol. 1 No. 1 2012, 312 23
Suwardi Endraswara, Falsafah Kepemimpinan Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2013), 23 24
Stephen R Covey, Principle-Centered Leadership (New York: Simon & Schuster, 1992), 78
23
Dalam kehidupan masyarakat Jawa pandangan itu menjadi satu kesatuan dan merupakan
bagian dari kehidupan. Demikian pula dalam politik. Di dalam kepemimpinan politik masyarakat
Jawa tercermin empat lingkaran yang disampaikan oleh Suseno di atas. Paling tidak hal itu dapat
diterjemahkan dalam tiga ciri model kepemimpinan masyarakat Jawa yakni mistik, kharismatik-
filosofis, dan eufemistis.25
Pertama, pola kahidupan mistik. Secara definitif mistik atau mistifikasi bermakna
mengaburkan, misterius dan menjadi teka-teki. Hal yang mistik cenderung kabur, gaib dan tidak
terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Bertolak dari penjelasan ini, mistik jika dikaitkan
dengan politik akan didapat sebuah pemahaman yang mengarah kepada sebuah aktifitas, tindakan
atau langkah-langkah politik yang tidak lazim ada pada aktifitas politik secara umum. Kepercayaan
animisme yang dianut masyarakat Jawa kiranya dapat dikaitkan dengan permasalahan “politik-
mistik” ini.
Berbagai literatur merekam, sejak zaman prasejarah masyarakat Jawa telah memiliki
kepercayaan animisme, yakni suatu kepercayaan terhadap roh yang terdapat pada benda-benda,
tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, atau juga manusia sendiri. Saat melakukan prosesi
penyembahan, masyarakat Jawa melakukan upacara dengan sesaji yang tentu erat dengan hal-hal
mistik dan gaib. Dalam upacara tersebut masyarakat Jawa juga menyertainya dengan bunyi-bunyian
dan tari-tarian. Kebiasaan lokal masyarakat Jawa ini memang tidak bisa dilepaskan begitu saja pada
masa-masa setelahnya. Ketika Islam datang, persentuhan dengan kebiasaan lokal suatu daerah,
menyebabkan Islam hadir dengan tetap mengakomodir atau disesuaikan dengan ajaran Islam. Mark
R. Woodward menuliskan bahwa Islam terutama yang berkembang di Jawa merupakan Islam yang
masih dilekati lapisan simbol tipis makna animistik dan atau tradisi Hindu-Budha.26
Corak keislaman yang dipresentasikan oleh Islam tradisional ini, dalam kajian pemikiran
Islam disebut sinkretis atau sinkretisme. Sinkritisme, secara etimologis berasal dari bahasa arab,
tepatnya kata syin dan kritozein yang berarti mencampuradukkan unsur-unsur yang bertentangan.
Ada juga yang menyebut bahwa sinkritisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu syncretism yang
dimaknai campuran, gabungan, paduan dan kesatuan. Berbicara sinkretisme kita akan dihadapkan
dengan dua tradisi atau lebih dengan percampurannya sebab adanya masyarakat yang mengadopsi
suatu kepercayaan baru dan berusaha untuk tidak terjadi benturan dengan apa-apa yang menjadi
kebiasaan lama.
John R. Bowen melalui tulisannya Religious Practice menjelaskan bahwa sinkretisme adalah
percampuran antara dua tradisi atau lebih yang terjadi ketika masyarakat mengadopsi sebuah agama
baru dan berusaha membuatnya tidak bertabrakan gagasan dan praktik budaya lama. Bertolak dari
25
Suwardi Endraswara, Falsafah Kepemimpinan Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2013), 35 26
Agus Dharma, Gaya kepemimpinan yang Efektif bagi Para Manajer (Bandung: Sinar Baru, 1984), 13
24
penjelasan ini potret kemistikan masyarakat Jawa memang berakar nun jauh hingga zaman pra
sejarah. Walau kepercayaan masyarakat berganti, dari HinduBudha dan kini memeluk Islam,
masyarakat Jawa tak ubahnya secara jamak masih tetap memercayai unsur-unsur mistik, gaib, hal-
hal yang secara rasional tidak bisa diterima.27
Karakteristik kekuasaan di Jawa hampir dapat dipastikan selalu berkaitan dengan hal yang
berbau gaib. Orang Jawa masih memegang teguh keyakinan adanya kekuatan lain di luar dirinya
yang dapat membantu atau memberikan pengaruh pada kekuasaan. Paling tidak ada dua
karakteristik yang melekat pada paham kekuasaan Jawa, seperti yang disampaikan Anderson dan
Setiwan. Karakter tersebut yakni sentralistik. Kekuasaan yang ada terkonsentrasi serta adanya
kecenderungan untuk mengambil hak kekuasaan lain. Dikarenakan sifat yang memusat tersebut
maka tidak akan ada kekuatan lain yang dibiarkan bebas dan terlepas dari kendali pusat kekuasaan,
sebab selain ada potensi mengganggu keseimbangan atau keharmonisan lingkaran kekuasaan, juga
secara ancaman yang terus mengintai sehingga membahayakan keberadaan pemegang kekuasaan
tersebut.
Ciri lain kekuasan yang bercorak mistik adalah kekuasaan yang dianggap berasal dari alam
ilahiah atau adikodrati yang tunggal, dan tidak berasal dari rakyat sebagaimana yang tercantum
dalam teori kedaulatan rakyat. Dampak dari pemahaman ini adalah tidak adanya sebuah pertanyaan
atau pengkritisan atas sah atau tidaknya kekuasaan tersebut diperoleh. Rakyat akan cenderung
tunduk saja, tidak macammacam sebab meyakini bahwa hal yang ilahiah atau adikodrati memang
suatu hal yang mutlak, tidak boleh ada pertanyaan atau pengkritisan. Pertanggungjawaban moral
pun akan sulit terjadi. Semisalpun ada bukan merupakan hasil dari hubungan kekuasaan antara yang
memerintah dengan yang diperintah, melainkan lebih sebagai bentuk tanggungjawab moral yang
ditumbuhkan dari dalam diri sendiri.
Para pemegang kekuasaan menurut paham kekuasaan Jawa menerima kekuasaan tersebut
dari sumber adikodrati, dan kekuasaan yang diterima tersebut dianggap sebagai amanat atau tugas
suci yang hanya mempunyai konsekuensikonsekuensi tertentu dengan sumber atau asal kekuasaan
dan bukannya dari pihak lain. Kedua karakteristik kekuasaan yang disebut di atas akan
memengaruhi perilaku elite politik. Semisal karakteristik pertama, yaitu kekuasaan yang cenderung
sentralistis. Pola ini akan kita dapati dalam cara-cara pengambilan keputusan elite politik dan
pemangku jabatan di setiap sektornya. Kecenderungan yang demikian menempatkan pemegang
posisi puncak sebuah kekuatan politik berperan sangat dominan atau menentukan dalam setiap
proses pengambilan keputusankeputusan. Oleh karenanya kontrol yang sangat ketat adalah
konsekuensi dari persepsi atas kekuasaan.
27
Sri Wintala Achmad, Falsafah Kepemimpinan Jawa: Dari Sultan Agung Hingga Hamengkubuwana IX
(Yogyakarta: Araska, 2018), 17
25
Karakteristik kedua, karena kekuasaan berasal dari alam adikodrati, hal yang ilahiah maka
tidak mempunyai ikatan moral secara horisontal, mengakibatkan pola pertanggungjawaban sebuah
keputusan atau kebijaksanaan elite kepada masyarakat umum juga tidak ada. Mungkin bisa saja
masyarakat didengar suaranya atau seolah-olah dibuat mereka ikut berpartisipasi dalam proses
pembuatan keputusan, namun pada prinsipnya, persepsi tentang kekuasaan seperti ini nyatanya
tetap menonaktifkan partisipasi arus bawah yang ada. Seperti telah disinggung di atas, bahwa
hadirnya corak Islam tradisional yang tetap menjadikan kebiasaan masyarakat Jawa untuk tetap
diakomodir dalam Islam. Ini membuat kepercayaan akan hal-hal mistik, berbau gaib tetap
terpelihara dalam model kepemimpinan masyarakat Jawa hingga kini.
Kedua, kharismatik-filosofis. Pola kepemimpinan sebagaimana yang tergambar pada
karakteristik dalam poin pertama mengakibatkan pola kepemimpinan yang kharismatik. Secara
etimologis kharismatik mempunyai makna suatu hal yang membuat seorang individu atas dasar
kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya membuat orang lain mempunyai rasa kagum atas diri
sang linuwih atau yang mempunyai kelebihan tersebut. Namun bukan berarti berpijak pada poin
pertama, seseorang langsung dapat dihormati dan disegani masyarakat. Ada beberapa catatan atau
hal-hal yang harus dipenuhi. Hal ini bisa diketahui dari apa yang telah dilakukan diejawentahkan
oleh pemimpin nusantara masa lalu.
Terkait ciri kharismatik dalam model kepemimpinan Jawa, dalam hal ini bisa dikaitkan
dengan pandangan Max Weber. Secara historis, Max Weber mengambil istilah charisma dari
perbendaharaan kata yang dipakai pada permulaan pengembangan agama Kristen guna menunjuk
satu dari tiga jenis kekuasaan dengan pengklarifikasian klasik. Weber membedakan antara pertama,
Kekuasaan tradisional atas dasar suatu kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi kuno.
Kedua, Kekuasaan yang rasional atau berdasarkan hukum (legal) yang didasarkan atas kepercayaan
terhadap legalitas peraturan-peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan, yang
berkuasa berdasarkan peraturanperaturan untuk mengeluarkan perintah. Ketiga, Kekuasaan
kharismatik yang didapatkan atas pengabdian diri atas kesucian, sifat kepahlawanan atau yang patut
dicontoh dari ketertiban atas kekuasaannya.
Lebih lanjut menurut Weber, walaupun istilah kharismatik pada masa kini berbeda dengan
ketiga hal lainnya namun tetap mempertahankan aspek loyalitas (pengabdian). Kharismatik diyakini
memiliki sesuatu yang luar biasa. Memimpin dengan cara yang tidak lazim dari sesuatu yang telah
dikenal. Serta mampu mematahkan hal-hal terdahulu untuk kemudian menciptakan hal-hal baru
bersifat revolusioner yang mampu tumbuh dalam keadaan serumit apapun. Dari segi
kemunculannya, kharisma yang disematkan pada seorang pemimpin lazimnya terlontar pada
persepsi rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, dapat didefinisikan kembali (tanpa keluar dari
26
maksud Weber yang hakiki) kharismatik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mendapatkan
kehormatan, ketaatan serta kehebatannya sebagai sumber dari kekuasaan tersebut dengan
penekanan dalam setiap interaksinya (antara pemimpin dan pengikutnya) harus terdapat suatu
integritas yang continue. Dengan kata lain, diwajibkan akan adanya kesadaran pada benak kita
untuk bersatu pada satu tujuan, satu keinginan, satu cita-cita, satu harapan dan satu perjuangan.
Kemudian, barulah kita berharap akan muncul sosok pemimpin kharismatik yang dicintai, dihargai,
dan dihormati. Tentu saja, pemimpin kharismatik adalah pemimpinan yang mampu menggandeng
semua kelompok, golongan, etnis, suku, agama dan siapapun saja untuk mendapatkan kesetiaan.
Menurut Conger dan Kanungo, karakteristik pemimpin yang karismatik adalah percaya diri,
memiliki visi yang jelas dan mampu mengungkapkannya, memiliki keyakinan yang kuat akan visi
tersebut, berkomitmen tinggi. Beberapa teori menganggap bahwa kharisma itu adalah suatu hasil
dari kemampuan memahami dan mempengaruhi bawahan, dan hanya bisa dilakukan oleh pemimpin
yang berkualitas dan memiliki perilaku yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat
itu. Berbagai teori karismatik memiliki penjelasan yang beragam mengenai proses-proses
memengaruhi yang terdapat di dalamnya. Penjelasan psikoanalitis dari kharisma menekankan pada
pengaruh dari pemimpin yang berasal dari identifikasi pribadi dengan pemimpin tersebut. Semisal
Teori atribusi kharisma menekankan kepada identifikasi pribadi sebagai proses utama dan
internalisasi sebagai proses sekunder.
Teori Meindle menjelaskan bahwa orang-orang yang pindah agama secara langsung
dipengaruhi oleh pemimpin, tetapi orang lain kemudian dipengaruhi melalui sebuah proses
penularan sosial. Teori dari House menekankan kepada identifikasi pribadi, pembangkitan motivasi
oleh pemimpin, dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan-tujuan dan rasa percaya diri para pengikut.
Teori konsep diri menekankan internalisasi nilai, identifikasi sosial, dan pengaruh pemimpin
terhadap kemampuan diri, dengan hanya memberi peran yang sedikit terhadap identifikasi pribadi.
Karakteristik kekuasaan dalam pemahaman Jawa yang berbentuk sentralistis atau memusat dan
diyakini berasal dari alam illahiah atau adikodrati yang tunggal semakin memperkuat sebagimana
yang disampaikan Weber.
Ketiga, bercorak eufemistis yang bermakna penghalusan dalam bertutur kata dan cenderung
berputar-putar. Clifford Geertz dalam The Religion of Java memaparkan karakter masyarakat Jawa
ini. Dalam tradisi Jawa, sifat “halus” baik dalam prilaku, perkataan, maupun tulisan menunjukkan
kepriyayi-an atau kejawaan seseorang. Dalam hal ini kalangan priyayi Jawa cenderung memakai
istilah-istilah eufemistik atau bahasa halus. Kata-kata keras dan bersifat langsung atau to the point
sebisa mungkin untuk dihindari, sehingga cenderung berputar-putar tidak mengena langsung pada
27
maksud. Karakter ini bisa dengan mudah kita temui dalam falsafah ataupun peribahasa yang beredar
di kalangan masyarakat Jawa.
Semisal Wong Jowo Nggone Semu, Sinamun Ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis,
Ngunu Ya Ngunu Ning Aja Ngunu, dan Ewuh Pekewuh. Ungkapan Wong Jowo nggone semu,
sinamun ing samudana, sesadone ingadu manis mempunyai makna orang Jawa cenderung
terselubung, ditutup kata-kata tersamar, masalah apapun dihadapi dengan manis. Santosa
menjelaskan berpikir dan bersikapnya orang Jawa tidak selalu terbuka atau dalam arti cenderung
bersifat simbolik. Pernyataan yang disampaikan masyarakat Jawa dipenuhi Sanepa, kiasan dan
perlambangan. Santosa melanjutkan, semisal ada pengemis datang, apabila tidak berkenan
menyisihkan sedikit hartanya, seorang yang didatangi itu biasanya akan menggelengkan kepala
sembari tersenyum. Bisa juga mengatakan Maklume Mawon (maafkan saja) untuk tidak mengatakan
“tidak” kepada si pengemis. Jadi cenderung disamarkan. Ada juga yang menggunakan kalimat
Sanese Mawon (lainnya saja) yang intinya sama untuk Sinamun Ing Samudana.28
3. Sifat Kepemimpinan Jawa
Menurut ajaran Kitab Dasa Dharma Sastera Gajah Mada dianggap mampu mewujudkan
sifat kepemimpinan Jawa yang hakiki. Dia mampu bertindak manjing ajur-ajer, artinya mau
merasakan penderitaan rakyat, mengayomi, ikut menghayati apa saja yang menjadi keluhan rakyat,
dan mampu menemukan jalan keluar. Dari karya besar itu, Gajah Mada mampu menjalankan
sepuluh sifat dasar kepemimpinan Jawa, yaitu:29
a. Rajin sujud, meditasi atau samadhi. Laku sujud atau disebut manembah, selalu menjadi
landasan bertindak. Memimpin yang disertai sujud, akan ingat selalu pada Sang Pencipta,
sehingga tidak gegabah dalam bertindak. Digambarkan bahwa sejak anak-anak, Gajah Mada
suka sujud atau meditasi. Meditasi sering dilakukan malam hari dan sering mendapatkan
vision (penglihatan) dewata yakni mendapat petunjuk dari dewa Brahma.
b. Awas (visioner), artinya menjadi pelopor dan memiliki wawasan ke depan. Gajah Mada
selalu menjadi pelopor dan mengambil inisiatif yang pertama serta bekerja keras di antara
teman-teman sebayanya. Cetusan ide cemerlang seorang pimpinan memang penting, biarpun
belum tentu disetujui bawahan. Ide yang visioner, dilandasi sikap awas, artinya tahu
berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kata lain, dia dapat menggabungkan dua
konsep kepemimpinan, yaitu
1) ngerti, artinya tahu berbagai hal
2) pakarti, artinya tindakan apa yang seharusnya diambil.
28
Khoirul Rosyadi, Mistik Politik Gus Dur (Yogyakarta: Jendela, 2014), 151 29
Suwardi Endraswara, Falsafah Kepemimpinan Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2013), 46
28
c. Greget, artinya tokoh pimpinan yang menjadi sumber motivator bawahan. Pimpinan yang
penuh greget, berarti mampu mendorong kemajuan bawahan. Paling tidak, dia mampu
memberi semangat dalam kerja keras dan berat, terutama dalam memajukan sistem
pertanian. Gajah Mada mampu memotivasi sesamanya. Kharismanya tampak sejak anak-
anak, kemana Gajah Mada pergi diikuti oleh temanteman sebayanya.
d. Babar binuka, artinya pimpinan yang benar-benar bersifat open manajemen. Kepemimpinan
yang terbuka jauh lebih dihargai bawahan. Ahli memimpin, termasuk memimpin sidang,
hatinya terbuka dan kata-katanya manis bagai air kehidupan. Dalam berbagai kesempatan
Gajah Mada digambarkan dapat memimpin sidang, memiliki keterbukaan dan memimpin
yang memberikan kesejukan kepada bawahannya. Pemimpin demikian hatinya halus, tidak
gemar nggetak-nggetak (memarahi) pada bawahan. Bawahan juga tidak akan banyak curiga
pada atasan.
e. Lantip, artinya pemimpin yang mampu menangani berbagai hal. Kelantipan pemimpin ini
yang disegani bawahan. Dia mampu menarik simpati, cerdas dan kreatif. Hal ini tampak
ketika Gajah Mada pertama kali mengabdikan dirinya di istana maha patih yang sudah mulai
tua yang bernama Arya Tadah, dan kemudian dia dikawinkan dengan putrinya yang
bernama Dyah Bebed. Kecerdasan Gajah Mada tampak pula ketika ia ingin mengetahui
wajah asli raja Bedahulu dengan cara minta dijamu sayur pakis yang utuh sedepa
panjangnya, lauk pauknya setumpuk usus ayam, minumnyasatu bumbung legen, ia bersedia
makan dihadapan raja. Dengan cara demikian itu Gajah Mada akan mudah melihat wajah
raja Bali pada saat itu, dan raja tidak boleh membunuh utusan raja Majapahit ini, apalagi
yang bersangkutan sedang menikmati makanan.
f. Sopan dan ramah. Gajah Mada sangat sopan dan ramah ketika ia ditanya oleh Kebo Wawira
(Kebo Iwa) dan Pasung Grigis tentang maksud kedatangannya ke Bali. Gajah Mada diutus
oleh raja Jawa yang mempunyai putri yang sangat cantik, tiada duanya di Wilatikta, dan
memuji Kebo Wawira (Kebo Iwa) supaya bersedia mengawini putri Jawa tersebut. Karena
penampilannya yang sopan dan ramah, akhirnya Kebo Wawira (Kebo Iwa) berhasil ditipu
oleh Gajah Mada.
g. Senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, tidak mementingkan kesukaan duniawi,
mempelajari kitab suci, dan melaksanakan upacara yadnya.
h. Senantiasa melindungi warga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan
keadilan.
29
i. Seorang pemimpin hendaknya gagah berani, bertanggung jawab, dan tangguh dalam
menghadapi berbagai masalah, tunduk kepada aturan (hukum). Tidak menghina rakyat
jelata, dan tidak menjilat kepada penguasa (atasan).
j. Menghormati orang bijaksana, menghargai para pahlawan, dan senantiasa melakukan
tapabrata dan semadhi.
Dari sepuluh sifat kepemimpinan itu, sebenarnya kalau dapat dilaksanakan bangsa ini akan
adil dan makmur. Jangakan sepuluh halite, dapat menjalankan lima saja, seorang pimpinan sudah
tergolong hebat. Pemimpin yang handal dapat menerapkan syarat-syarat tersebut dalam sikap dan
perilakunya. Ajaran itu penting bagi pimpinan, tetapi jika tanpa implementasi juga tidak ada artinya.
Kalau diperhatikan, hampir seluruh ajaran kepemimpinan itu memuat idealism dan gagasan mulia.
4. Sintesis Mistik Kepemimpinan Jawa
Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang,
terutama dalam kehidupan beragama dan berbudaya.30
Sebelum kedatangan Islam dan Barat
(terutama Belanda), Jawa beberapa ratus tahun lamanya dibawah kerajaan Hindu Buddha, dan
mereka menancapkan agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Jawa merupakan etnik
terbesar di Asia Tenggara. Etnik ini berjumlah kurang lebih empat puluh persen dari dua ratus juta
penduduk Indonesia. Seperti sebagian besar penduduk Indonesia, 85 % lebih juga memeluk agama
Islam. Tetapi sudah bisa diduga, pemeluk agama yang sedemikian masif itu, berbeda-beda secara
kultural, bukan karena keanekaragaman yang begitu besar di kalangan orang Indonesia, tetapi juga
karena variasi subkultur di lingkungan orang Jawa sendiri.31
Pada umumnya, orang Jawa percaya bahwa semua penderitaan akan berakhir bila telah
muncul Ratu Adil. Kepercayaan akan benda-benda bertuah serta melakukan slametan merupakan
upaya orang Jawa untuk melakukan harmonisasi terhadap alam sekelilingnya. Selain itu, inti dari
ajaran kejawen adalah amemayu hayuning bawana, yang dimuat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha.
Menjelaskan ajaran ini, Mpu Kanwa menggambarkan tugas seorang pimpinan yang harus
memperbaiki dan memakmurkan dunia, seperti dinyatakan dalam Pupuh V bait 4-5. Sunan
Pakubuwana IX (1861-1893) mengubah bait tersebut dalam serat Wiwaha Jarwa menjadi “Amayu
jagad puniki kang parahita, tegese parahita nenggih angecani manahing Iyan wong sanagari
puniki” (melindungi dunia ini dan menjaga kelestarian parahita, arti parahita ialah menyenangkan
hati orang lain di seluruh negeri ini).
Tugas hidup amemayu hayuning bawana, oleh Ki Ageng Suryamentaram dan Ki Hajar
Dewantara, dikembangkan menjadi mahayu hayuning bangsa, mahayu hayuning bawana
(memelihara dan melindungi keselamatan pribadi, bangsa, dan dunia). Tugas amemayu hayuning
30
Ibid., 152 31
Cliford Geertz, The Religion of Java (New York: Free Press, 1964), 34
30
bawana jelas merupakan kewajiban bagi setiap orang sebagai pemimpin. Tradisi Jawa,
“Jawanisme” atau “Kejawen” bukanlah suatu katagori religius. Namun ia lebih merujuk pada
sebuah etika atau sebuah gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Jawa. Sehingga, ketika sebagian
orang mengungkap kejawaan mereka, pada hakikatnya hal itu adalah suatu karakteristik yang secara
kultural condong pada kehidupan yang mengatasi keanekaragaman religius.32
Pengalaman Mulder ketika melakukan penelitian di Yogyakarta, ia menemukan seorang
muslim yang taat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, tetapi mereka tetap orang Jawa
yang membicarakan mitologi wayang, atau menafsirkan shalat lima waktu sebagai pertemuan
pribadi dengan Tuhan. Banyak diantara mereka menghormati slametan sebagai mekanisme integrasi
sosial yang penting, atau sangat memuliakan ziarah makam orang tua dan leluhur mereka. Apa yang
dikemukakan Mulder, juga diperjelas oleh Woodward.
Dalam penelitiannya tentang Islam Jawa ditemukan beberapa aspek penting yang
membedakan Islam Jawa dengan praktik Islam lain. Pertama, Islam Jawa mengharuskan agar ritus-
ritus peralihan kehidupan khitanan, perkawinan, dan kematian harus dilaksanakan sesuai dengan
hukum Islam, tetapi juga berpegang pada aspek lain dari kesalehan syariat-centris yang merupakan
suatu hal yang bebas pilih. Di dalam hal ini, penerapan mikrokosmos/makrokosmos ke dalam
pemikiran kosmologis, keagamaan, politik dan sosial mentransformasikan watak mistisisme sufi.
Di Jawa, struktur jalan mistik memainkan peran dominan dalam pemikiran kosmologis
sosial, politik dan tradisional. Kedua, baik Islam normatif maupun berbagai versi desa Islam Jawa
berkaitan dengan kepercayaan kraton (royal cult). Hubungan antara syariat dan doktrin mistik
adalah suatu tema paling penting dalam teks-teks keagamaan yang menjadi dasar agama kraton.
Tetapi ada kalanya Islam normatif sesuai dengan syariat, tetapi ada pula syariat tidak terpakai
kesemuanya.33
Dalam mempraktikkan agama dalam kehidupan sosial, masyarakat Jawa dikenal sebagai
masyarakat yang pintar dan canggih. Terutama dalam menciptakan sintesis mistik dan agama dalam
ruang sosial. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari para pemimpinnya, seperti Wali, Raja, dan
Sultan yang secara cerdik mampu mengkonversi tradisi Islam ke dalam tradisi Jawa. Menurur
Ricklefs, inilah salah satu titik kunci keberhasilan Islamisasi di Jawa. Masyarakat Jawa telah
mengembangkan sebuah budaya literer yang dan religius yang canggih serta diperintah kaum elite
yang berfikiran cukup jauh sebelum Islam tercatat muncul untuk pertama kalinya dalam masyarakat
Jawa pada abad-14. selanjutnya tradisi tersebut diperkuat dan diperteguh oleh Islam, dan menjadi
salah kekuatan dalam proses Islamisasi.
32
Suwardi Endraswara, Falsafah Kepemimpinan Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2013), 143 33
Mark R. Woodward Woodward, Islam Jawa Kesalehan Normatif (Yogyakarta: LKiS, 2004), 16
31
Konversi budaya dalam Islam, selain Wali Songo, juga tidak dapat dilepaskan dari tokoh
utama, yakni raja terbesar di Jawa Sultan Agung (1613-1646). Dalam sejarah Sultan Agung dikenal
mampu mempertemukan dan mendamaikan keraton dengan tradisi Islam. Sultan tidak lantas
memutus hubungannya dengan Ratu Kidul (Nyi Roro Kidul) penguasa laut selatan, tetapi dia juga
mengambil langkah yang tegas terhadap Islamisasi di Jawa. Meskipun dalam sejarah, rintisan
canggih Sultan Agung tidak secara sistemik dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, namun apa yang
dia dilakukan merupakan langkah besar dalam menghubungan antara agama dan budaya Jawa.
Karena sesudah era Sultan Agung, Jawa menghadapi beragam persoalan, mulai konflik antar
keluarga, antar kerajaan hingga berhadapan dengan imperialis Belanda. Keberhasilan Sultan Agung
dalam mengawinkan agama dan tradisi, melahirkan apa yang disebut Rickleft sebagai “Sistesis
Mistik”.34
Sistesis Mistik memuat tiga pilar utama, suatu kesadaran identitas islami yang kuat, menjadi
Jawa berarti menjadi muslim, pelaksanaan lima rukun ritual dalam Islam secara sungguh-sungguh
dan konsekwen serta penerimaan terhadap realitas kekuatan spritual khas Jawa seperti Nyi Roro
Kidul dan Sunan Lawu. Bersamaan dengan kedatangan Islam, maka tradisi yang sudah sangat kuat
dianut oleh masyarakat Jawa selanjutnya memperoleh tempat melalui justifikasi keagamaan lewat
bebarapa aktor. Pemimpin Jawa seperti Wali, sultan, kiai dan santri merupakan aktor penting yang
meperkuat posisi dimaksud. Demikian pula dalam kepemimpinan politik formal dan birokrasi.
34
Jati Nur Cahyo, “Makna Simbolik Tokoh Wayang semar Dalam Kepemimpinan Jawa”, Jurnal Media Wisata Vol. 16
No. 2 November 2018, 1073
32
BAB III
MANUSKRIP KYAI AGENG IMAM PURO
A. Biografi Kyai Ageng Imam Puro
1. Sejarah Kyai Ageng Imam Puro
Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 yang di deklarasikan oleh Raden Bathara
Katong. Nama Ponorogo berasal dari kata Pramana dan Raga. Pramana atau Pana yang artinya
mengerti, atau wasis, rahasia hidup, wadi, mumpuni. Sedangkan Raga artinya Jasmani, badan,
keseluruhan atau fisik. Jadi nama Ponorogo dapat ditafsirkan berarti dibalik badan wadak manusia
itu tersimpan suatu rahasia hidup (wadi) berupa oleh batin yang mantap dan mapan berkaitan
dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, shufiah, dan muthmainah.1
Pendiri Kadipaten Ponorogo adalah Bathara Katong yang masih merupakan putra dari Prabu
Brawijaya V raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raden Bathara Katong dalam pemerintahannya juga
dibantu oleh Ki Ageng Mirah, Patih Seloaji, dan para Warok Ponorogo.2 Raden Bathara Katong
turut mensyiarkan agama Islam di Ponorogo. Sepeninggal Bathara Katong, Kadipaten Ponorogo
dipimpin oleh penerusnya. Salah satunya adalah Raden Tumenggung Surabrata yang memimpin
Ponorogo pada masa Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo karena Geger Pacinan. Salah satu
pertimbangannya adalah karena kekuatan militer Adipati Ponorogo Surobroto saat itu sangat kuat
daripada milik Adipati Madiun.
Dalam masa pelariannya ke Ponorogo, Sunan Pakubuwono II menggunakan gelar Panembahan
Brawijaya. Ini berarti secara tidak langsung Sunan Pakubuwono II menganggap dirinya sebagai
keturunan Sunan Lawu (Raden Gubtur atau Raden Gugur), putra Prabu Brawijaya V penghabisan
dari Majapahit).3
Pada hari Sabtu Wage, tanggal 27 Rabiul Akhir tahun Alip 1667 atau tanggal 30 Juli 1742
Masehi Sunan Pakubuwono II dan para rombongannya melarikan diri ke arah timur dan sampai ke
Kabupaten Ponorogo. Dalam perjalanan tersebut sesekali Sunan Pakubuwono II dan rombongan
beristirahat guna melepas lelah dan mengisi tenaga. Menurut tutur cerita masyarakat Ponorogo, ada
banyak tempat di Kabupaten Ponorogo yang sempat di singgahi oleh Sunan Pakubuwono II selama
1 Tim Penulis, Hari Jadi Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Pemda Ponorogo, 1996), hlm. 8.
2 Warok adalah sosok orang yang dituakan, disegani, dan orang yang dihormati oleh masyarakat Ponorogo. Warok
berasal dari kata wewarah. Warok adalah wong kang sugih wewarah. Artinya, seseorang menjadi warok karena mampu
memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok adalah orang yang sudah
sempurna dalam laku hidupnya, dan sampai pada pengendapan batin. Herry Lisbijanto, Reog Ponorogo. (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2013), hlm., 20. Sedangkan menurut Babad Ponorogo, Warok berasal dari bahasa Arab, Waroi, artinya
pimpinan. Bahasa Jawanya Wirangi, yang artinya sudah paham, sudah mengerti sekali kepada kasar halusnya lahir
batin. Warok perbuatan hidupnya hanya untuk menolong masyarakat dan negara, karena Allah. Baca juga
Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid VII. 1985. hlm 49. 3 Dwi Ratna N, dkk, op.cit, hlm. 73.
33
masa pelarian. Seperti cerita masyarakat Badegan berikut ini, rombongan Sunan Pakubuwono II
ketika beristirahat disana oleh masyarakat setempat disuguhi badeg (air ketan). Sunan Pakubuwono
kemudian memberikan nama daerah ini dengan nama Badegan.4
Perjalanan kemudian dilanjutkan dan sampailah Sunan Pakubuwono II beserta rombongan
melewati perkampungan yang tertata rapi dan terdapat pula alun-alun disana. Ternyata sesepuh dari
daerah ini bernama Jayenggrana. Sunan Pakubuwono II dan rombongan sempat singgah dan
beristirahat di kediaman Jayenggrana. Sunan Pakubuwana II meyakini bahwa Jayenggrana masih
mempunyai silsilah keturunan orang besar (tedhaking kusumu rembesing madu). Kemudian Sunan
Pakubuwono II mengajak Jayenggrana mengikuti perjalanan Sunan Pakubuwono II ke daerah
Ponorogo.5 Mulai dari sinilah Jayenggrana kemudian menjadi pendamping dan penunjuk arah
Sunan Pakubuwana II selama berada di Ponorogo. Tempat tinggal Jayenggrana akhirnya bernama
Dukuh Jayenggrana masuk Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo.
Selanjutnya, rombongan Sunan Pakubuwono II melanjutkan perjalanannya dan melewati
sebuah hutan lebat. Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk singgah sebentar untuk beristirahat
dan bertapa. Alas duduk Sunan Pakubuwono II adalah batu persegi pipih dan lebar. Tempat itu
dikemudian hari bernama Pertapan, sekarang masuk Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan
Ponorogo. Sedangkan batu tempat alas duduk tersimpan di Pemakaman Tamanarum.6
Ketika Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo, banyak pengikutnya kemudian yang ingin
tinggal dan menetap di Ponorogo. Salah satunya adalah Wonodikromo yang kemudian babad alas di
Ponorogo. Datang lagi rombongan dari Pajang berjumlah 6 keluarga, yaitu Sumodriyo,
Surosentono, Surodihardjo, Kromodrono, Mangundriyo, dan Singomarto.7 Joko Pitono adalah salah
satu pengikut Pakubuwono II yang datang ke Ponorogo. Joko Pitono memilih untuk tinggal
menetap di Ponorogo dan babad di wilayah yang dekat dengan sungai yang sekarang jadi Kelurahan
Pinggirsari. Pengikut dari Pakubuwono II yang lain adalah Raden Tumenggung Mangkuwijoyo
yang ikut menemani rajanya bertapa di Hutan Mangkujayan. Senopati prajurit Kartasura yang
bernama Elang Lawet atau Pronojoyo dan para prajurit menempati Mangkujayan bagian barat
tepatnya di daerah Prajuritan. Ada juga Kyai Nologati salah satu pengikut dari Pakubuwono II yang
kemudian menetap di Kelurahan Nologaten sekarang.8
Adipati Ponorogo, Raden Surabrata, mendengar keberadaan Susunan Pakubuwono II.
Adipati Surobroto secepatnya melacak, akhirnya bertemu di sebelah barat kota. Susunan
4 Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid III: R. Brotodiningrat, (Ponorogo: Depdikbud, 1985), hlm. 21.
5 Ibid.
6 Ibid, hlm. 22.
7 R. Purwowijoyo, Babad Kandha Wahana: 19 Desa Kecamatan Ponorogo, (Ponorogo: Dep. Pendidikan dan
Kebudayaan Ponorogo, 1990), hlm. 29. 8 Ibid, hlm. 40-42.
34
Pakubuwono II dimohon menuju ke Pendopo Kabupaten tetapi Sunan belum berkenan. Dalam
rombongan Sunan Pakubuwono II juga terdapat orang Belanda, yaitu Hoogendrorp.9 Namun,
Hoogendorp kemudian melanjutkan perjalanannya ke Surabaya dan kemudian ke Batavia untuk
melapor pada pemerintah VOC.
Perjalanan Sunan Pakubuwono II berlanjut ke timur dengan diikuti Jayengrana sebagai
penunjuk jalan. Sebagai hiburan kadang perjalanan itu diselingi dengan berburu (bebedag). Tempat
beliau berkenan berburu sekarang bernama Dusun Bedagan, Desa Pulung. Sehari tidak mendapat
satu burungpun dan kemudian turun hujan. Sunan Pakubuwono II memakai payung (songsong).
Tempat memakai payung ini kemudian dinamakan Dukuh Sepayung.10
Pengikut Sunan
Pakubuwono II juga ada yang kemudian menetap di Pulung, tepatnya di Desa Serag yang termasuk
bagian dari Desa Kesugihan. Pengikut Sunan Pakubuwono II di Desa Serag bernama Kyai Sera
yang berkeinginan untuk hidup sendiri, karena itu atas perkanan Sunan Pakubuwono II beliau
kemudian babad hutan di desa yang masih asing tidak berpenghuni.11
Malam hari beliau beristirahat di bukit kecil (puthuk alit). Di tempat itu beliau tampak pucat
seperti mayat (layon), maka tempat tersebut bernama Selayon. Di tengah malam beliau melihat
sebuah cahaya (pulung) jatuh. Tempat menghilang cahaya itu ternyata tempat tinggal (padhepokan)
orang yang sudah tua. Sunan Pakubuwono II mendekati rumah tinggal tersebut. Setelah
mengucapkan salam beliau memasuki tempat tinggal tersebut. Pemilik rumah itu adalah seorang
empu yang bernama Empu Salembu. Empu Salembu menunjukkan bahwa cahaya tadi masuk ke
dalam kotak. Sunan Pakubuwono II memerintahkan Jayenggrana untuk membuka kotak tersebut
dan isinya adalah pedang yang merupakan milik dari Empu Salembu sendiri.12
Empu Salembu kemudian menyerahkan pusaka itu yang mempunyai kekuatan untuk
menjaga ketenteraman Negara. Sunan Pakubuwono II kemudian menyerahkan pusaka itu kepada
Jayenggrana. Empu Salembu juga mengajak Sunan Pakubuwono II dan Jayenggrana ke tempat
pembuatan pusakanya. Tempat pembuatan pusaka dari Empu Salembu kemudian dinamakan
Besalen. Sedangkan tempat tinggal Empu Salembu dinamakan Desa Pulung.13
Menjelang pagi
Sunan Pakubuwono II mau berwudhu untuk sholat Subuh. Melihat blumbang (sumur dangkal
berbentuk lebar) begitu besar seperti segara (laut). Akhirnya tempat itu dinamakan
Segaran.14
Perjalanan Sunan Pakubuwono II dan rombongan kemudian menuju ke arah wilayah
9 Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid III: R. Brotodiningrat, op.cit, hlm. 22.
10 Ibid.
11 E.M. Shodieq, Pulungku, (Ponorogo:Nirbita, 1984), hlm. 49
12 Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid III: R. Brotodiningrat, op.cit, hlm. 22-23.
13 Ibid, hlm. 24.
14 Ibid.
35
Gunung Bayangkaki. Disana Sunan Pakubuwono II bertemu saudaranya yaitu Pangeran Kalipo
Kusumo yang sudah lama bertapa dan menetap di Pegunungan Bayangkaki.
Gunung Bayangkaki merupakan gunung yang tidak aktif yang terletak di Desa Temon,
Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Gunung Bayangkaki terdiri dari empat puncak. Urutan
puncak jika dilihat dari sebelah utara adalah sebagai berikut, aling timur bernama puncak atau
Gunung Ijo, puncak yang kedua bernama puncak atau Gunung Tuo, yang nomor tiga bernama
Puncak Tumpak atau Puncak Bayangkaki, sedangkan yang ujung barat dinamakan puncak atau
Gunung Gentong. Keempat puncak tersebut memiliki keindahan alam yang menakjubkan.15
Ada
beberapa goa yang ada di Gunung Bayangkaki, antara lain:
a. Goa Watu Tutup, dipakai sebagai rumah dan tempat bertapanya Pangeran Kalipo Kusumo.
b. Goa Putri Piningit, dipakai sebagai tempat beristirahat oleh para putri yang menjadi istri
sang pangeran.
c. Goa Dandang, dipakai sebagai tempat untuk memasak.
d. Goa Lumbu.
e. Goa Lawa.
Rombongan Sunan Pakubuwono II kemudian bertemu dengan Pangeran Kalipo Kusumo di
Gunung Bayangkaki. Pangeran Kalipo Kusumo adalah putra Pakubuwono I dari Kartosuro. Beliau
menjauhkan diri dari keramaian masyarakat. Untuk itu Pangeran Kalipo Kusumo pergi bertapa di
Gunung Bayangkaki di daerah Kabupaten Ponorogo. Selama Pangeran Kalipo Kusumo melakukan
tapa di Gunung Bayangkaki keadaan masyarakat di sekitarnya kelihatan sangat tentram, dan hasil
tanaman sangat memuaskan dan semuanya terhindar dari segala gangguan hama. Di samping itu,
Pangeran Kalipo Kusumo mempunyai sifat suka menolong kepada sesamanya. Oleh sebab itu
beliau sangat disenangi dan dihormati serta disegani oleh penduduk di sekitar Gunung Bayangkaki
tempat Pangeran Kalipo Kusumo bertapa.16
Dalam pertemuan Sunan Pakubuwono II dengan Pangeran Kalipo Kusumo itu, Sunan
menceritakan segala hal yang terjadi sehingga membuat dirinya harus melarikan diri dari Keraton.
Mendengar penjelasan Sunan Pakubuwono II itu, maka tertegunlah Pangeran Kalipo Kusumo.
Setelah diam sejenak mulailah Pangeran Kalipo Kusumo memberikan petunjuk agar adiknya
bersedia melakukan tapa di bawah pohon Sawoo (Sawoo sak kembaran) yang terletak di sebelah
selatan Gunung Bayangkaki.
15
Alip Sugianto, Eksotika Pariwisata Ponorogo, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm. 117. 16
Sebagai peringatan akan jasa-jasa Pangeran Kalipo Kusumo terhadap penduduk sekitar itu, maka diadakanlah upacara
labuhan dengan makan bersama di Krapyak tersebut pada hari Jumat Legi setelah hujan bersama. Lihat di, Gatot
Murniatmo dan H.J Wibowo, Beberapa Peninggalan Budaya di Daerah Ponorogo, (Yogyakarta: Balai Penelitian
Sejarah dan Budaya, 1981), hlm. 37-38.
36
Sunan Pakubuwono II kemudian mematuhi anjuran dari Pangeran Kalipo Kusumo untuk
bertapa di bawah pohon Sawoo.17
Sekarang ini petilasan tempat bertapa Sunan Pakubuwono itu
masih ada dan disebut petilasan Sunan Kumbul.18
Di daerah itu Sunan Pakubuwono II mendapat
sajian gula sebesar sawo dibagi dua. Ada pula seorang janda yang menyajikan kacang. Daerah itu
kemudian dinamakan Dusun Kacangan.
Pangeran Kalipo Kusuno sendiri hanya bisa membantu perjuangan adiknya dari tempat
pertapaannya yaitu Gunung Bayangkaki. Sebab beliau telah bersumpah tidak akan meninggalkan
Bayangkaki sampai akhir hayatnya. Untuk itulah maka setelah mendekati umur tua, Pangeran
Kalipo Kusumo bila naik ke puncak Bayangkaki memerlukan waktunya membuat lubang kubur
yang disediakan untuk dirinya sendiri.19
Beliau berpesan pada para pengikutnya kelak apabila
saatnya meninggal supaya dikuburkan di puncak Bayangkaki.
Setelah Pangeran Kalipo Kusumo wafat, maka oleh para pengikutnya jenazah Pangeran
Kalipo Kusumo dibawa ke puncak Gunung Bayangkaki untuk dimakamkan disana. Jenazah
Pangeran Kalipo Kusumo diangkat oleh orang-orang laki-laki tua (kaki-kaki, dalam bahasa Jawa).
Cara membawanya diangkat bersama-sama dengan hati-hati (dibayang-bayang, dalam bahasa Jawa)
yang akhirnya selamat tiba di tempat. Oleh sebab itu gunung tempat Pangeran Kalipo Kusumo
dimakamkan disebut Bayangkaki.20
Adapun putra-putri dari Pangeran Kalipo Kusumo adalah:21
a. Raden Mas Lelah, dikenal sebagai Mbah Lelah tinggal di Desa Kori.
b. Raden Mas Dumeling, tinggal di Gunung Pegat Tugurejo.
c. Raden Adirasa, dimakamkan di Desa Tugu Mlarak.
d. Raden Surodongsa, di makamkan di Bayangkaki.
e. Raden Setroikromo, dimakamkan di Desa Kori.
Sementara itu, setelah bertemu dengan Pangeran Kalipo Kusumo dan bertapa di Sawoo,
rombongan Sunan Pakubuwono II melanjutkan perjalanan ke Pondok Gerbang Tinatar di Desa
Tegalsari. Pondok Gerbang Tinatar yang berada di Desa Tegalsari kemudian menjadi tempat
persinggahan rombongan Sunan Pakubuwono II. Pondok dan Masjid Tegalsari ini didirikan oleh
Kyai Mohammad Besari sekitar abad ke-18 atas perintah dari gurunya yaitu Kyai Donopuro.22
Kyai
Mohammad Besari berasal dari Caruban dan merupakan murid dari Kyai Donopuro yang
17
Sunan Pakubuwono II kemudian bertapa dengan duduk di atas bonggol sawo. 18
Gatot Murniatmo dan H.J Wibowo, op.cit, hlm. 38. 19
Ibid. 20
Ibid. 21
Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid V: Desa Perdikan, (Ponorogo: Depdikbud, 1985), hlm. 49. 22
Tempat belajar para santri di Pondok Gerbang Tinatar dahulu berada di Angkringan (Pondok sederhana dari bambu).
37
mempunyai Pondok di Setono.23
Kyai Mohammad Besari sendiri masih keturunan dari Majapahit,
sebagai berikut:
a. Raja Brawijaya V
b. Retno Manik, menikah dengan Adipati Gelang Kediri
c. Demang Irawan Kediri
d. Raden Demang Kediri
e. Kyai Ngabdul Mursat (Kyai Ageng Tukun)
f. Kyai Ageng Anom di Caruban
g. Kyai Ageng Mohammad Besari di Tegalsari
Sunan Pakubuwono II beserta rombongan diterima dengan senang hati oleh Kyai
Mohammad Besari. Sunan Pakubuwono II dan rombongan beristirahat di kediaman Mohammad
Besari yang letaknya tidak jauh dari Pondok Gerbang Tinatar dan Masjid Tegalsari. Para santri
pondok saat itu juga siap membantu rombongan Sunan Pakubuwono II selama berada di Tegalsari.
Sunan Pakubuwono II kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada
Kyai Mohammad Besari. Sunan Pakubuwono II juga meminta nasehat serta doa kepada Kyai
Mohammad Besari supaya diberi kesabaran dan diberikan kekuatan supaya bisa mengatasi semua
masalah yang sedang dihadapinya. Kyai Mohammad Besari kemudian mengajak Sunan
Pakubuwono II untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan
dalam mengatasi cobaan ini.24
Setelah mendapat dukungan dan kekuatan moril dari Kyai Mohammad Besari, rombongan
Sunan Pakubuwono II pamit untuk kembali ke Keraton Kartasura. Keputusan ini diambil karena
pasukan bantuan yang sedang berperang melawan pasukan aliansi Tionghoa-Jawa berada di atas
angin dalam pertempuran. Sunan Pakubuwono II kemudian kembali ke Keraton Kartasura dengan
diikuti oleh beberapa santri terpilih, yaitu Hasan Besari, Bagus Harun Basyariah, dan Imam Puro.
Rombongan Sunan Pakubuwono II. Hasan Besari adalah cucu dari Kyai Mohammad Besari putra
dari Kyai Ilyas. Bagus Harun Basyariyah adalah putra dari Kyai Ageng Prongkot di Tosanan,
Somoroto. Kyai Ageng Prongkot putera Raden Imam di Mataram. Raden Imam Putera Raden
Pringgalaya di Mataram. Pangeran Pringgalaya putera Panembahan Senapati, Raja Mataram.25
Sedangkan Imam Puro yang makamnya ada di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, adalah putra
23
Kyai Donopuro masih keturunan dari Sunan Tembayat. Desa Tegalsari berasal dari Pedukuhan Sentono yang
statusnya berubah menjadi Desa Setono yang terletak di sebelah barat Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Kyai Donopuro
dan Pangeran Sumende adalah yang babad di Setono pertama kali, kemudian mendirikan masjid dan pondok. Lihat di
Suwarno, Kekunaan Masjid Tegalsari Ponorogo, Jawa Timur, PATRAWIDYA, Vol. VII, No. 4, Desember 2007. 24
R. Purnomo, Kyai Ageng Besari di Sewulan Madiun, (Ponorogo: K.U.A.D.T. II Ponorogo, 1961), hlm. 18. 25
Purwowijoyo, Babad Ponorogo Jilid III: R. Brotodiningrat, op.cit, hlm. 25.
38
dari Abu Yamin dari Pangeran Bagus Pasai. Kyai Imam Puro kemudian menurunkan beberapa
generasi sebagai berikut:26
a. Kyai Imam Puro II
b. Nyai Imam Besari
2. Kesenian Kebo Bule Kyai Ageng Imam Puro
Kebo Bule Kyai Slamet adalah hewan langka yang menjadi hewan klangenan dari Sunan
Pakubuwono II.27
Menurut GKR. Timoer Rumbai, Sunan Pakubuwono II sebelumnya bersemedi di
daerah Ponorogo kemudian mendapat petunjuk ada benda pusaka yang diberi nama Kyai Slamet
yang dapat dijadikan media dalam mensejahterakan kehidupan pada saat itu, tapi syaratnya satu,
Sunan Pakubuwono II harus mencari kerbau warna putih yang gunanya untuk mengawal atau
mendampingi benda pusaka tersebut. Bupati Surobroto yang tahu akan hal itu, kemudian
mencarikan Kebo Bule di wilayah Kadipaten Ponorogo dan memberikannya kepada Sunan
Pakubuwono II.28
Setelah Adipati Ponorogo memberikan Kebo Bule kepada Sunan Pakubuwono II, pusaka
Tombak Kyai Slamet kemudian dimasukkan kedalam binatang langka tersebut. Kebo Bule Kyai
Slamet kemudian ikut dibawa rombongan Sunan Pakubuwono II ke Keraton Kartasura. Para santri
Kyai Mohammad Besari dari Tegalsari juga ikut, yang terkemuka adalah Hasan Besari, Bagus
Harun Basyariyah, dan Imam Puro.
Ketika Sunan Pakubuwono II mencari tempat kerajaan baru sebagai pengganti Keraton
Kartasura, Sunan Pakubuwono II memerintahkan Patih Pringgalaya dan Sindureja melakukan
penelitian bersama Mayor van Hoogendrorp. Turut pula para ahli nujum yaitu Kyai Tumenggung
Honggowongso, Raden Tumenggung Paspanagara, dan Raden Tumenggung Mangkuyuda.29
Mereka menemukan tiga tempat, yaitu Desa Kadipala, Desa Solo, dan Desa Sanasewu, dan mereka
menentukan Desa Solo yang layak dipilih. Namun, Sunan Pakubuwono II masih belum yakin
dengan hasil musyawarah tersebut. Manurut Insiwi Febriari Setiasih, ada satu andil yang dilakukan
Kebo Bule dalam menentukan lokasi baru kerajaan tersebut. Ketika diumbar, Kebo Bule kemudian
26
Silsilah Kyai Imam Pura yang peneliti dapatkan dari keluarga keturunan Imam Puro di Dusun Danyang, Desa
Sukosari, Kecamatan Babadan. 27
Wakit Abdullah, Javanese Language and Culture in the Expression of Kebo Bule in Surakarta: An Ethnolinguistic
Study, Jurnal Komunitas 8 (2): 285-294. 28
Hasil wawancara Sindy Nuranindya dengan GKR. Timoer Rumbai, 50 tahun, Pengageng keputren Keraton
Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sindy Nuranindya, Kebo Bule: Makna Kebo Bule Kyai Slamet Pada Ritual Kirab
Pusaka Satu Suro Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Skripsi, (UNAIR: Antropologi FISIP, 2016). 29
Dwi Ratna N, dkk, op.cit, hlm. 73.
39
berjalan menuju Desa Solo dan memakan rumput disana. Oleh sebab itu, maka Sunan Pakubuwono
II yakin bahwa Desa Solo cocok untuk dijadikan keraton yang baru.30
Maka dari itu, Kebo Bule menjadi binatang peliharaan yang istimewa dan keramat di
Keraton Surakarta dari masa ke masa. Kebo Bule adalah simbol kekuatan yang secara praktis bagi
masyarakat berbasis agraris digunakan sebagai alat pengolah pertanian, sumber mata pencaharian
hidup bagi masyarakat Jawa. Kerbau juga mempunyai nilai tinggi dalam sebuah ritual, karena
kerbau-kerbau ini dinilai oleh masyarakat sekitar memiliki kekuatan ghaib karena kerbau tersebut
dianggap keramat.31
Keturunan Kebo Bule Kyai Slamet kemudian menjadi icon Keraton Kartasura setiap
diadakan Kirab Pusaka malam satu Suro. Kebo Bule Kyai Slamet menjadi cucuk lampah karena
dianggap keramat. Barisan kirab pusaka ini didahului oleh barisan Kebo Bule lalu diikuti dengan
barisan benda-benda pusaka yang dibawa oleh abdi dalem dan sentana dalem yang telah ditunjuk
oleh raja untuk membawa benda pusaka tersebut.32
Rute yang mereka lewati pada saat Kirab adalah dari Kamandungan, menuju ke Alun-Alun
Utara, Gladhag, Sangkrah, Jl. Pasar Kliwon, Gading, Gamblegan, menuju Nonongan, ke jalan
protokol Slamet Riyadi, ke arah timur menuju ke Gladhag, lalu masuk melalui Alun-Alun Utara,
menuju kembali ke Kamandungan. Rute yang mereka lewati tersebut adalah daerah kekuasaan
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kirab tersebut memakan waktu selama kurang lebih 4
jam sejak dari keluar Kamandungan hingga kembali ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Meskipun
begitu, masyarakat yang ingin menyaksikan dengan segala kepercayaan mereka, banyak pula yang
menunggu dari sebelum Kirab dimulai hingga kirab tersebut selesai.33
Menurut penuturan Srati Kebo Bule yang bernama Ngabehi Mulyo Pradito dalam Majalah
Djaya Baya tanggal 18 April 1999, jika ada pedagang sayuran, jika ada dagangannya di makan oleh
Kebo Bule merasa bahagia sekali. Hal itu menandakan barang dagangannya akan laris. Jadi, di
pasar Kebo Bule bisa bebas memakan apapun sekehedaknya.34
Nilai kesejarahan yang terkandung dalam Sejarah Kebo Bule Kyai Slamet, mampu kembali
menjelaskan bagaimana hubungan harmonis antara Kabupaten Ponorogo dan Kasunanan Surakarta
sudah lama terjalin. Kebo Bule Kyai Slamet yang diberikan Adipati Ponorogo yaitu Raden
Tumenggung Surobroto sebagai wadah pusaka Kyai Slamet yang diperoleh Sunan Pakubuwono II
30
Riza Ayu Purnamasari, Fenomena Kebo Bule Kyai Slamet Dalam Kirab 1 Suro Keraton Kasunanan Surakarta,
Skripsi, (UNS: Program Ilmu Komunikasi FISIPOL, 2014), hlm. 105. Hasil wawancara dengan Insiwi Febriari Setiasih,
pada 10 Juli 2012, di Kampus FSSR UNS. 31
Sindy Nuranindya, op.cit, hlm. 10. 32
Ibid, hlm. 55. 33
Ibid, hlm. 43. 34
“1 Suro Manut Tradisi Jawa”, Djaya Baya 29, Minggu Pon, 18 April 1999.
40
ketika bersemedi di Ponorogo, menjadi simbol yang bisa bertahan lintas generasi sampai sekarang
ini.
Dari penjelasan diatas tersebut, kemudian memberikan inspirasi kepada Silahudin Hudaya,
S.Pd yang beralamat di Dusun Danyang, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo, untuk membuat kesenian Kebo Bule Kyai Slamet. Kesenian Kebo Bule Kyai Slamet ini
dibuat sebagai pengingat sejarah besar yang pernah terjadi ketika Raja Kartasura Sunan
Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo akibat Geger Pacinan. Peristiwa besar ini jangan sampai
dilupakan oleh generasi penerus kita dan supaya bisa diambil hikmahnya dari sejarah yang terjadi
untuk kebaikan di masa yang akan datang.
Kesenian tradisional Kebo Bule Kyai Slamet merupakan kesenian rakyat yang bersifat
kesenian jalanan (Street arts) karena dalam pertunjukannya diarak berjalan mengelilingi
perkampungan masyarakat. Dalam pentasnya kesenian ini berjalan sambil diiringi oleh irama
lantunan musik religi yang menyiratkan pesan-pesan moral dalam masyarakat.
Sebelum pentas kesenian Kebo Bule Kyai Slamet ini, terlebih dahulu diadakan sebuah rapat
dan latihan dihalaman masjid bisa jadi pindah tempat sesuai keinginan dari temen temen selaku
pemerkasa paguyuban guna mengecek persiapan, kondisi personil maupun perawatan Kebo Bule
Kyai Slamet agar dalam pentasnya berjalan maksimal.
B. Identifikasi Naskah Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
1. Inventarisasi Naskah
Dalam penelitian ini, inventarisasi naskah dilakukan yaitu naskah manuskrip Kyai Ageng
Imam Puro sebagai sumber data penelitian. Setelah melakukan pengamatan naskah yang diteliti
secara langsung dan sudah melihat kondisi naskah, maka ditetapkan naskah naskah manuskrip Kyai
Ageng Imam Puro sebagai sumber data penelitian.
2. Deskripsi Naskah
Merupakan uraian atau gambaran keadaan naskah secara fisik dengan teliti dan diuraikan
secara terperinci. Selain melakukan deskripsi naskah, peneliti sebaiknya juga melakukan deskripsi
teks. Deskripsi teks merupakan garis besar isi teks yang meliputi bagian pembukaan, isi, dan
penutup teks. Naskah dan teks dideskripsikan dengan pola yang sama, yaitu nomor naskah, ukuran
naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, dan garis besar isi teks35
. Berikut deskripsi naskah
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro :
a. Judul : Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
Naskah ini sebenarnya tidak berjudul karena tidak ditemukan kata yang menunjukkan
judul atau sebagai cover dari naskah tersebut. Setelah itu penulis memberikan nama naskah
35
Nabilah Lubis, Naskah, Teks, & Metode Penelitian Filologi (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Depag RI, 2007).
58
41
ini sesuai dengan nama penulisnya yaitu Kyai Ageng Imam Puro, jadi judul naskah ini adalah
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro.
b. Penulis : Pennulis naskah ini ialah Kyai Ageng Imam Puro
c. Penyimpanan naskah : penyimpanan naskah saat ini di rumah bapak Marwan, Dusun
Krajan Desa Sukosari
d. Asal-usul Naskah : Naskah ini merupakan tulisan tangan dari Kyai Ageng Imam Puro,
kemudian setelah beliau meninggal di wariskan kepada santrinya yaitu Mbah Mad
Semangun kemudian di wariskan kembali kepada anaknya yang bernama Mbah
Karsoikromo kemudian di wariskan ke anaknya yang bernama Mbah Kromo Miran
kemudian di wariskan kembali kepada anaknya yang bernama Mbah sikir kemudian di
wariskan kembali kepada anaknya yang bernama Bapak Marwan, hingga saat ini naskah
itu masih di simpan oleh Bapak Marwan.
e. Keadaan: tidak terawat, karena naskah ini tidak di bersihkan dari debu dan kotoran serta
tempat penyimpananya pun kurang baik untuk naskah tersebut. Naskah ini disimpan di
lemari yang keadaanya sangat lembap yang mengakibatkan banyak jamur yang ada pada
naskah tersebut. Ada beberapa lembar bagiannya yang sudah sobek, khususnya dibagian
awal banyak yang sudah sobek.
f. Cover: naskah manuskrip Kyai Ageng Imam Puro ini tidak memiliki cover naskah, yang
ada adalah halaman depan naskah yang berupa halaman kosong.
Gambar 3.1 Halaman depan naskah
g. Cover Belakang: naskah ini tidak memiliki bentuk cover belakang tetapi dalam akhir
naskah ini terdapat salah satu kalimat penutup yang diambil dari ayat al-Qur’an yaitu surah
42
al-Hu >d ayat 6 dan 56. Kalimat penutup ini pada intinya adalah Kyai Ageng Imam Puro
berpesan bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini akan di jamin rezekinya oleh Allah
Swt.
Gambar 3.2 Halaman belakang naskah
h. Ukuran Naskah :
1) Ukuran Naskah : 17 cm x 21 cm
2) Ukuran Teks : 12,5 x 16 cm
3) Margin Atas : 2 cm
4) Margin Bawah : 3 cm
5) Margin Kiri : 3 cm
6) Margin Kanan : 2 cm
i. Halaman Naskah : 82 halaman
j. Huruf dan Tulisan :
1) Jenis Tulisan : Teks ini ditulis dengan Aksara Arab-Pegon
2) Ukuran Huruf : Cukup Besar dan Stabil.
43
3) Bentuk Huruf : Arah Letak Huruf tegak.
4) Keadaan Tulisan : Jelas dan mudah dibaca.
5) Bekas Pena : Tebal.
6) Jarak antar huruf : Rapat dan rapi.
7) Warna Tinta : Hitam.
8) Peggunaan Tanda Vokal (Harakat)
Aksara yang digunakan adalah Arab-Pegon oleh karena itu dalam
mengklasifikasikan aksara sesuai dengan aksara Arab-Pegon, tapi untuk beberapa cuplikan
dari al-Qur’an ditulis sesuai huruf Arab.
Tabel 3.1 Aksara Arab-Pegon
Alif :
Ba> :
Ta> :
Tsa> :
Ji>m :
Ha> :
Kha> :
Dal :
Dzal :
Ra> :
Za> :
Si>n :
Shi>n :
Sha>d :
Da>d :
Ta> :
Z}a> :
‘Ain :
Ghain :
Fa> :
Qa>f :
Ka>f :
La>m :
Mi>m :
Nu>n :
Wa>w :
Ha> :
La>m-Alif :
Hamzah :
Ya> :
Aksara Arab yang dipakai untuk aksara Pegon antara lain :
اب ت ج د ر س ط ع ف ك ل م ن و ه ي
Aksara Pegon merupakan huruf konsonan yang digandeng dengan huruf vokal dan
sandangan huruf lain. Untuk menjadikan huruf vokal maka harus ditambahkan huruf vokal
yaitu, Alif (ا) : untuk bunyi A, Ya (ي) : untuk bunyi I, Wawu (و) : untuk bunyi U, Serta
44
harus ditambah sandangan (bantu) yaitu fathah ( َ ) , pȇpȇt (~) dan Hamzah (ء). Kaidah –
kaidah aksara Pegon adalah sebagai berikut:
a) Huruf Jim ( ج) ditambah 2 titik menjadi/dibaca Ca/C
Contoh: Wacakake (Dibacakan) ditulis
b) Huruf Dal (د) diberi 3 titik di atas menjadi/dibaca Dha/Dh
Contoh: Sumedheng (Sedang) ditulis
c) Huruf Ya (ي) ditambah 2 titik menjadi/dibaca Nya/Ny
Contoh: Penyaket (Penyakit) ditulis
d) Huruf Kaf (ك) ditambah 3 titik dibawah menjadi/dibaca Ga/G
Contoh: Penggaweyane (Pekerjaannya) ditulis
e) Huruf ‘Ain (ع) ditambah 3 titik diatas menjadi/dibaca Nga/Ng
Contoh: Irung (Hidung) ditulis
f) Huruf Pegon ditambah alif (ا) berbunyi A, contoh أ/ها maka dibaca Ha/A
Contoh: Anganiyaya (Menganiaya) ditulis
g) Huruf Pegon ditambah Ya (ي) berbunyi I
Contoh: Budi (Budi/Akhlaq) ditulis
h) Huruf Pegon digandeng dengan Wawu (و) untuk bunyi O
Contoh: Wong (Orang) ditulis
45
i) Huruf Pegon diberi sandangan Pȇpȇt (~) atau tidak diberi sandangan apapun
dibaca Ê
Contoh: Derengki (Dengki) ditulis
9) Penggunaan tanda baca:
a) Awal bab pembahasan
Disetiap awal pembahasan diawali dengan kata Kitab
b) Titik. Titik ini menggunakan huruf Ha
c) Akhir bab pembahasan
Disetiap akhir pembahasan ditutup dengan kata Tamat Wawlahua’lam
k. Cara Penulisan
1) Lembaran yang digunakan naskah tulisan ini dengan bolak-balik (recto-verso).
Selanjutnya ditulis pada kedua halaman, yakni muka (recto) dan belakang (verso).
2) Penempatan isi teks pada lembaran naskah ditulis rapi sejajar dengan lembaran
naskah.
3) Tata letak ruang tulisan, larik-lariknya ditulis secara berdampingan dan rapi.
l. Bahasa Naskah
Jenis bahasa yang dipakai naskah ini ialah Bahasa Jawa baru dan ragam bahasanya
ialah Jawa Ngoko. Bahasa jawa baru artinya tidak bersifat statis, meskipun digunakan sejak
sekitar 500 tahun lalu, diperkirakan awal prasati Sukabumi di daerah Kediri, Jawa Timur.
Sedangkan bahasa Jawa baru ini yang dituturkan dan ditulis pada zaman Majapahit dianggap
lebih ke arah Bahasa Jawa Modern karena banyak mengalami hampir setengah perubahan36
.
Bahasa Jawa baru ini bisa dilihat dalam penggunaan imbuhan kata e seperti Kendhel
m. Bahan Kertas Naskah :
1) Jenis : Lokal
2) Macam : Polos
36
Siti Baroroh Baried, dkk, Pengantar Teori Filologi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 14
46
3) Kualitas : Tebal dan kuat
4) Warna : Kuning kecoklat-coklatan
n. Umur Manuskrip : 200 Tahun lebih.
C. Ringkasan Isi Naskah Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro, merupakan karya monumental yang pernah ditulis oleh
Kyai Ageng Imam Puro. Manuskrip ini berisi tentang pembahasan agama Islam perspektif al-
Qur’an, Hadits maupun sejarah para ulama. Penulisan Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro diawali
dengan pembahasan tema-tema tertentu, sedangkan pembahasan Manuskrip tersebut antara lain :
1. Halaman 1 Cover
2. 2-10 tentang Pupuh Asmorondono. Inti bab ini adalah tentang petuah agar menjadi orang yang
baik budinya serta ajaran tentang ilmu sejati yang membuat hati tentram.
3. Halaman 11 Lembar Kosong
4. 12-35 tentang Hadist Nabi Muhammad saw. Dalam bab ini membahas tentang keberkahan
umat Nabi Muhammad Saw yang meninggalkan fitnah.
5. Halaman 36-37 Lembar kosong.
6. Alaman 38-49 tentang kisah raja Ismail bin Ahmad.
7. Halaman 50-51 Gambar wayang.
8. Halaman 52-58 tentang Nashoihul Muluk (nasehat kepada Raja-raja).
9. Halaman 59-61 tentang Adabus Salathin (adab atau etika seorang penguasa).
10. Halaman 62-77 tentang serat Angger-anggeran yaitu Perjanjian antara keraton Yogyakarta dan
Keraton Solo.
11. Halaman 78 Do’a Kebangsaan.
12. Halaman 79 lembar kosong
13. Halaman 80 tentang amalan pengobatanal-Qur’an penyakit batu karang
14. Halaman 81 tentang ayat al-Qur’an ayat ke 56 Surah Hud yang dijadikan sebagai penutup kitab
dan pada intinya adalah berpesan untuk bertawakkal kepada Allah swt.
15. Halaman 82 tentang coretan-coretan pengarang dan menurut penulis halaman ini dimaksudkan
untuk dijadikan sebagai sampul belakang.
D. Suntingan Naskah
Suntingan teks adalah teks yang telah mengalami pembetulan dan perubahan sehingga
bersih dari bacaan yang korup. Salah satu tujuan dari penyuntingan teks dalam penelitian ini supaya
teks dibaca dengan mudah oleh kalangan yang lebih luas berikut suntingan teks manuskrip Kyai
Ageng Imam Puro :
47
1. Huruf kapital digunakan untuk menulis ungkapan untuk Tuhan, unsur nama orang, nama
tempat, dan nama tahun-bulan-hari. Maka dari itu, kata ataupun kelompok kata yang tidak
memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, akan ditulis menggunakan huruf kecil
atau biasa (bukan kapital).
2. Pembagian alenia/paragraf dalam suntingan teks, berdasarkan interpetrasi penulis.
3. Pemakaian tanda hubung (-) untuk penulisan kata ulang (reduplikasi) dalam teks.
4. Pemakaian tanda koma (,) dan titik pada teks (.) berdasarkan pada interpretasi penulis, karena
tanda koma pada teks asli hanya digunakan untuk mengakhiri sebuah pembahasan dalam satu
bab, sedangkan titik pada teks asli biasanya hanya digunakan untuk mengakhiri sebuah bab
pembahasan.
5. Tanda /é/ digunakan untuk menandai vokal e yang dibaca [e] seperti pengucapan kata “kowé”
dalam Bahasa Jawa dan kata “enak” dalam bahasa Indonesia.
6. Dalam mentranselitarisakan teks dalam suntingan ini untuk yang selain, maqāla Arab dan ayat
al-Qur‘an menggunakan pedoman penulisan pegon.
7. Sedangkan maqālah Arab dan ayat al-Qur‘an menggunakan transeliterasi Mc. Gill University.
8. Untuk halaman menggunakan halaman terus bukan recto-verso.
Berikut adalah sajian suntingan teks manuskrip Kyai Ageng Imam Puro setelah
mengalami berbagai tahapan dalam penulisan ini:
Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk. Ikilah kitab ingdalem anyatakaken ing caritane ing dadya
becike para ratu. Lan angucapaken pertingkahe ratu ana ing karaton donya kang pinilih iya
ratu iku dening Allah ta’ala saking sakehe manungsa donya kabeh khale den gadhekaken tur
dinadekaken ratu lan sinerahan ratu ing sakehe kawulaning Allah lan sinerahan ratu iki ing
sakehe kamulyan lan kaagungan lan sinerahan kinon angreksa ing kawula balane lan kinon
angeling-elingi kang becik lan aja lali-lali sira kabeh ing kawulaning Allah ta’ala lan kinon
angreksa ing sakehe ratu lan kagungan kang den pasrahaken marang sira kabeh para ratu
poma aja kongsi eling sakehe wewengkas kang ana ing sira para ratu maka lamun ana para
ratu iku gemi nestiti olehe anglakoni pakon angreksa [52] ing kawula balane kabeh maka
dadya mulya para ratu iki ana ing donya lan ing akherat saking kareksane olehe angreksa ing
kawulane Allah lan kang tinindhakaken dening Allah ta’ala marang para ratu kang ginawe
kawula ala iki kabeh.
Lan sebab dene kareksane artane Allah kang den serahake marang para ratu iku kabeh
apatah dene marang kawula balane maka dadya luwih luhur luwih mulya darajate saking
sakehe wong iku kabeh, lan sinungan kanugrahan. Lamun ana wong iku cilik maka orana wong
iku kabeh oleh kabecikan ora oleh kabecikan saking lobane lan ora eling saking sakehe barang
48
penggaweyane saking bangete bodhone khale ora pantes parentahe lan penggaweane patrape
marang sakehe kawulaning Allah lan marang sakehe arta kang ana para ratu kabeh maka
dadya lebur luwih eling ora karuan [53] maka dadya kalakuane ratu iku dadi ina lan wuwuh
alane lan kaya mangkono upamane anane ratu kaya upamane wong sawiji kang ginadhekaken
dening ratu dinadekaken gedhe anduweni sasigar nagara. Lamun ora becik penggaweane lan
parentahe maka akhir-akhire dadya rusak. Lan tatkala sira kawruhe martabate karaton ing
sakehe para ratu kang wus kasebut ngarep iku menggah bab pratingkahe kaagungan lan
kabecikan ingdalem penggawean kang ana sajerone karaton maka pahirsaken malih denira ing
pasal kang teka buri iki amihasaken ing sawirasatae ajar iki.
Utawi anapun ingdalem Kitab Adāb al-Mulūk maka sayogya urip ana sarate wong kang
dadya ratu iki anglakoni ing [54] sapuluh perkara maka kena ingucapaken ratu. Kang dhihin,
arep ana ratu iki duwe ngakal sarta kalawan budine kang bangsa sarngi, darapun bisaa ratu
iki ambedakaken ing becik lan ala. Lan kapindho, iki arep ana ratu iku anduweni ngelmu,
maka lamun ana ratu iku ora duwe ngelmu maka arepataa ratu iku anganthia wong kang ahli
ngelmu. Lan lamun ora anganthi wong duwe ngelmu, maka anguwatana ing kitab kang
anyaritakaken ing paprentahan saking sakehe ratu kang ngadil. Lan lamun ora bisa amaca ing
kitab iku maka akona amaca ing wong liyan kang bisa amaca, maka amiharsakena sira kabeh
wong kang padha dadya ratu ing sakehe wicarane kitab iki lan sira eling-elinga ing
sawicarane kitab iku sawuse sira piharsa maka sira turuta ajare kitab iku. Maka lamun ora
kaya mangkono maka dadya siya-siya olehe dadya ratu, [55] tan paedah dadya ratu tan kena
ingarep-arep ing donya akherat.
Lan kaping telu, iki arep ana sakehe mantri iku ngakil balig darapun yaktiya olehe ing
penggaweane ratu-ratu iku kabeh. Lan kapapat, iki arep ana ratu iku bagus rupane sarta becik
pakartine supaya yen padha asiha sakehe kawula balane ratu iku. Lan kaping lima, arep ana
ratu iku murah karana kang murah iku bangsane trah-trahe wong becik dadya wuwuh dana
lawan karamate kang bangsa sarngi kaya upamane mangkono wong kang bagus rupane. Lan
kaping nem, arep ana ratu iki anitenana ing penggaweane wong kang becik marang dheweke
ratu iku tatkala wong iku kasusahan maka arep den welasana kalawan kabecikan kaya
mangkono kang kinarepaken dening ratu iku.
Lan kaping pitu, iki arep ana ratu iku wani darapun anaa sakehe manteri iku [56] lan
ulubalang wani kabeh sarta kalawan ngaskara, tegese prajurit, iku padha melua wani. Lamun
ana ratu iki jerih maka yekti sakehe ngaskare iya melu jerih. Lan kaping wolu arep ana ratu
iku angurang-ngurangi pangan lan turu karana satuhune wong angakeh-akehaken mangan
turu iku dadya anarik ing bodhone hikmah anane karana satuhune Kitab Hikmah anyatakaken
49
maka sing sapa wonge angakeh-akehaken mangan maka yekti akeh-akeh turune temah
wekasan dadya kaluputan lan nelongsa saking sabarang penggaweane kang bangsa donya lan
kang bangsa akherat.
Lan kaping sanga, iki arep ana ratu iku angurang-ngurangi jima’ marang rabine lan
sapapadhane kalawan sukan-sukan rabine, karana satuhune penggawean kang mangkono iku
angapesaken ing badan kabeh lan andadekaken ing penyakit lan angurangaken ngakal. Lan
[57] kaping sepuluh, iki arep ana ratu iku lanang lan arep orana ratu iku wadon, karana ratu
wadon iki kurang ngakale lan malih ora winedenan saking sakehe mantrei lan ulubalang sarta
ora layak ratu wadon iki kaya pocapan kang kaucap ana ing jerone Kitab ‘Aqā’id al-
Muslimūn. Tamat wallāhu a’lam
Wa ṣāḥibu hādha Imām Pura wa kātibuhu huwa. [58]
Kitāb Adāb al-Salāṭīn. Ikilah kitab ingdalem anyatakaken tata kramane sakehe wong
kang dadya ratu utawa tumenggung utawa bekel. Kang ngadil kang wus kalakon ing zaman
kang dhihin-dhihin ingdalem saben-saben dina iki yogyane tinurut dening sakehe para ratu
kang kari-kari, para tumenggung kang kari-kari, para bekel kang kari-kari, maka ana kang den
lakokaken iki patang perkara penggaweane. Kang dhihin, iki arep gawea ngibadah ing Allah
ta’ala. Lan kapindho, iki iku amriksaa ing penggaweane wong kang anganiyaya lan wong kang
kena niyaya lan arep angira-ngiraaken ing nagarane lan arep cecelathon kalawan wong
ngalim lan sapapadhane iku kabeh. Lan kaping telu, iki arep ana penggaweane ratu iku tatkala
arif yen amangan lan aturu. Lan kaping pat, iki arep ana penggaweane ratu iku ameng-
amengan sanjata utawa lalancangan jaran utawa lelepasan panah [59] utawa ameng-amengan
pedhang lan tameng. Tamat.
Kitāb Adāb al-Salāṭīn. Ikilah kitab ingdalem anyatakaken tata kramane ratu kang
rahayu iya iku arep anglungguhe ing sapangendikane darapun kenaa ingarep-arep dening
wong akeh-akeh lan darapun dadya sukane wong iku kabeh marang sang ratu iku. Utawi
lamun ana ratu iku ora panggih ing barang pangandikane utawa ing barang parentahe maka
dadya ina ratu iku, tegese kena ingarep-arep pangandikane ratu iku maring wong akeh lan
dadya sinengitan dening wong akeh ratu iku. Utawi anapun lamun arep asare ratu iku maka
angaliha marang enggon liyan lan akon ratu iki ing wong sawiji yen anuronana ing paturone
sang ratu iki ingdalem saben-saben wengi, karana ratu iku akeh-akeh satrune. [60] Kawruhana
denira ing satuhune caritane sakehe ratu kang ngadil saking sakehe para nabi lan para wali
lan para solih lan para mu’min lan padha wedia ing Allah subḥānahu. Eh eling-eling sira
kabeh para ratu ing sakehe caritane Kitāb Tāj al-Salāṭīn.
50
Tamat wallāhu a’lam
Allāhumma aḥfiẓ lana fulānat mā dāma fī baṭniha ṣūratan ḥasanatan jāmilatan
kāmilatan wa thabbit fī qalbihi īmānan bika wa birasūlika mā dāma fī ḥayātihi fī al-dunya wa
al-ākhirati, Allāhumma akhrijhu. [61]
E. Terjemahan Naskah
Terjemahan adalah penggantian bahasa yang satu dengan bahasa yang lain atau pemindahan
makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa
sumber ke dalam bahasa sasaran. Terjemahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
terjemahan harfiah, terjemahan isi atau makna, dan terjemahan bebas. Berikut ini terjemahan
naskah manuskrip Kyai Ageng Imam Puro :
KITĀB NAṢĀIḤ AL-MULŪK
Inilah kitab yang menerangkan cerita agar menjadi baiknya para raja. Dan menyatakan
tingkah laku raja di kerajaan dunia, dan raja tersebut pilihan Allah dari manusia dunia
seluruhnya. Raja ini diberi gadai serta dijadikan raja dan diserahi pangkat raja bagi seluruh
umat Allah, dan diberikan kepada raja tersebut seluruh kemuliaan dan keagungan supaya ia
mampu menjaga seluruh hamba dan balanya, dan agar ia mengingat kebajikan, dan jangan
sampai ia melupakan hamba Allah dan mampu menjaga sesuatu yang ia disuruh menjaganya
dan menjaga semua apa yang sudah diserahkan kepada kalian hai para raja, maka ingat-ingatlah
apa yang sudah diamanatkan kepada kalian. Maka jika raja itu teliti dalam melaksanakan
perintah untuk menjaga [52] seluruh hamba dan balanya, maka raja ini akan mendapat
kemuliaan di dunia dan di akhirat sebab dari ia menjaga hamba Allah dan apa yang telah
diperbuat oleh Allah ta’ala kepada para raja yang berasal dari seluruh hamba yang buruk.
Sebab dijaga oleh Allah yang diserahkan oleh raja berserta pengikutnya maka menjadi lebih
luhur dan mulia derajatnya dari semua orang dan selalu dalam anugrah. Jika ada orang kecil
dalam tanggung jawabnya tidak ada kebaikan dalam pekerjaan seorang pemimpin karena
kebodohannya dan tidak pantas perintah dan pekerjannya terhadap semua makhluknya Allah
dan semua uang yang ada dalam penguasaan raja maka menjadi lebur dan sia-sia [53] maka
menjadi raja yang hina dan buah kesalahannya dan seperti itu perumpamaan seseorang yang
dijadikan raja yang diberikan sebagian negara. Jika tidak baik pekerjaannya dan perintahnya
maka pada akhirnya akan menjadi rusak. Saat kamu mengetahui martabat keraton dari semua
raja yang sudah disebutkan didepan bahwa bab perilaku, keagungan dan kebaikan didalam
pekerjaan yang ada dalam keraton maka perhatikan kembali dalam pasal atau pembahasan
sebelum dan selanjutnya yang akn di sampaikan.
51
Ini adalah kitab Adab Al-Muluk maka seyogyanya hidup syarat menjadi raja untuk
melakukan [54] 10 perkara sebagai berikut. Pertama, seorang raja yang berakal sehat serta
akhlaqnya yang mencerminkan syariat bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, seorang raja
harus berilmu jika tidak berilmu maka akan menjadi hina dan seharusnya diganti dengan
seseorang yang berilmu. Jika tidak diganti seorang yg berilmu maka berpegang teguhlah
dengan kitab yang menceritakan pemerintahan yang adil dan jika tidak bisa membaca kitab ini
maka mintalah seseorang yang bisa membaca dan menjelaskan tentang menjadi raja sesuai
dalam kitab ini dan ingat-ingatlah pembahasan dikitab ini sesudah mempelajari kitab ini dan
ajarkanlah kitab ini, maka jika tidak begitu akan siya-siya selama menjadi raja yang [55] tidak
berfaedah, jadilah raja yang menjadi panutan di dunia dan akhirat. Ketiga, pemimpin yang aqil
baligh artinya mengerti dengan semua apa yang dilakukan. Keempat, raja yang bagus dan
rupawan fisiknya dan baik perilakunya supaya bisa mengasihi seluruh rakyatnya. Kelima, raja
yang dermawan karena dermawan merupakan keturunan orang baik dan jadilah pelopor
penegak syariat seperti perumpamaan orang yang bagus rupawan. Keenam, raja yang teliti
dengan pekerjaannya yang baik serta peduli dengan orang yang kesusahan dan seperti itulah
yang diharapkan saat menjadi raja. Ketujuh, raja yang berani dari seluruh menterinya [56] dan
ulubalang serta seluruh rakyatnya harus berani, jika raja penakut maka sungguh seluruh
rakyatnya ikut penakut. Kedelapan, raja yang ahli puasa bahwa sesungguhnya orang yang
banyak makan dan tidur itu menarik dalam kebodohan hikmah karena dalam kitab hikmah
menyatakan barang siapa memperbanyak makan maka sungguh banyak kesalahan dan
kesengsaraan dari semua urusan dunia dan akhiratnya. Kesembilan, raja yang mengurangi jima’
terhadap istrinya karena hal tersebut dapat mendatangkan kerusakan badan dan mendatangkan
penyakit serta mengurangi akal.[57] Kesepuluh, raja dari jenis kelamin laki-laki dan bukan
perempuan karena raja perempuan kurang akalnya dan kurang menghormati para menteri dan
ulubalang serta tidak layak raja itu perempuan seperti yang diucapkan dalam cerita di kitab
‘Aqaidul Muslimun. Tamat wallāhu a’lam
Wa ṣāḥibu hādha Imām Pura wa kātibuhu huwa. [58]
KITĀB ADĀB AL-SALĀṬĪN
Ini adalah kitab yang menerangkan tata krama seseorang sebagai ratu, tumenggung,
atau bekel yang adil pada zaman dahulu. Hal ini setiap harinya sebaiknya ditiru oleh para raja,
tumenggung, dan bekel saat ini, yang harus dilakukan adalah empat perkara berikut. Pertama,
beribadah kepada Allah ta’ala. Kedua, memeriksa perbuatan aniaya dan orang yang teraniaya,
menganalisa negaranya serta komunikatif dengan para alim dan sepadannya. Ketiga, sebaiknya
52
seorang raja harus mengurangi makan dan tidur. Keempat, memainkan senjata, pacuan kuda,
panahan [59] atau memainkan pedang dan tameng. Tamat.
Kitāb Adāb al-Salāṭīn. Inilah kitab yang menerangkan raja yang selamat, kedudukan
dan sabdanya selalu dinantikan oleh orang banyak yang menjadikan orang banyak menyukai
sang raja. Jika sang raja tidak komitmen terhadap apa yang diucapkannya atau perintahnya
maka hinalah raja tersebut. Artinya sabdanya akan ditunggu orang banyak namun ia akan
dibenci oleh orang banyak.
Jika seorang raja ingin beranjak tidur maka hendaknya ia tidur di tempat lain dan
menyuruh orang lain agar tidur di tempat tidurnya setiap malam, karena raja itu selalu banyak
musuhnya. [60] Ketahuilah cerita-cerita para raja yang adil dari para nabi, para wali, para saleh,
dan para mukmin serta takutlah kepada Allah swt. Dan ingat-ingatlah kalian semua cerita para
raja yang tertulis dalam kitab Tāj al-Salāṭīn.
Tamat wallāhu a’lam
Allāhumma aḥfiẓ waladu fulānat mā dāma fī baṭniha ṣūratan ḥasanatan jāmilatan
kāmilatan wa thabbit fī qalbihi īmānan bika wa birasūlika mā dāma fī ḥayātihi fī al-dunya wa
al-ākhirati, Allāhumma akhrijhu. [61]
54
BAB IV
KONSEP KEPEMIMPINAN ISLAM-JAWA
DALAM MANUSKRIP KYAI AGENG IMAM PURO
A. Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk (Integritas Moral Pemimpin)
Kata integritas dalam bahasa Latin adalah “integrate”, artinya komplit, utuh dan sempurna
(tidak ada cacat). Integritas adalah tanpa kedok, bertindak sesuai dengan yang diucapkan, konsisten
antara iman dan perbuatan, antara sikap dan tindakan. Dalam konteks ini, integritas adalah rasa
batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter.1 Sedangkan
menurut kamus besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran.2 Sedangkan secara etimologi istilah moral berasal dari bahasa Latin
mos, moris (adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan) mores (adat istiadat, kelakuan,
tabiat, watak, akhlak). Moral berasal dari Bahasa Latin yaitu Moralitas adalah istilah manusia
menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif.3
Pemimpin yang berintegritas moral adalah pemimpin yang tanpa kedok, yang bertindak
sesuai dengan ucapan, sama di depan dan di belakang publik, konsisten antara apa yang di imani
dan kelakuannya, antara sikap dan tindakan,antara nilai hidup yang dijalani, tanpa kompromi,
pemimpin yang matang dan berintegritas berfokus untuk mencapai tujuan Allah. Moral dalam
zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap
amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral adalah produk dari budaya dan Agama.
Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya pada hatinya
sendiri. Pemimpin yang berintegritas moral selalu berpikir dan akan bertanggung jawab atas
keputusan yang dia ambil.4 Seperti dalam naskah manuskrip Kyai Ageng Imam Puro halaman 52 :
Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk. Ikilah kitab ingdalem anyatakaken ing caritane ing dadya becike
para ratu. Lan angucapaken pertingkahe ratu ana ing karaton donya kang pinilih iya ratu
iku dening Allah ta’ala saking sakehe manungsa donya kabeh khale den gadhekaken tur
dinadekaken ratu lan sinerahan ratu ing sakehe kawulaning Allah lan sinerahan ratu iki ing
sakehe kamulyan lan kaagungan lan sinerahan kinon angreksa ing kawula balane lan kinon
angeling-elingi kang becik lan aja lali-lali sira kabeh ing kawulaning Allah ta’ala lan kinon
angreksa ing sakehe ratu lan kagungan kang den pasrahaken marang sira kabeh para ratu
poma aja kongsi eling sakehe wewengkas kang ana ing sira para ratu maka lamun ana para
ratu iku gemi nestiti olehe anglakoni pakon angreksa ing kawula balane kabeh maka dadya
mulya para ratu iki ana ing donya lan ing akherat saking kareksane olehe angreksa ing
1 https://indrasetiawan17.wordpress.com/2022/02/02/definisi-integritasdan-pengertian-integritas-indolibrary/
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia
3 Bagus lorens, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 672
4 Ade Herlan Wahyudin, “Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita Dan Fakta”, AN-NIDHOM Volume 1 No. 1
(Januari-Juni) 2016, 19
55
kawulane Allah lan kang tinindhakaken dening Allah ta’ala marang para ratu kang ginawe
kawula ala iki kabeh.
Inilah kitab yang menerangkan cerita agar menjadi baiknya para raja. Dan menyatakan
tingkah laku raja di kerajaan dunia, dan raja tersebut pilihan Allah dari manusia dunia
seluruhnya. Raja ini diberi gadai serta dijadikan raja dan diserahi pangkat raja bagi seluruh
umat Allah, dan diberikan kepada raja tersebut seluruh kemuliaan dan keagungan supaya ia
mampu menjaga seluruh hamba dan balanya, dan agar ia mengingat kebajikan, dan jangan
sampai ia melupakan hamba Allah dan mampu menjaga sesuatu yang ia disuruh menjaganya
dan menjaga semua apa yang sudah diserahkan kepada kalian hai para raja, maka ingat-
ingatlah apa yang sudah diamanatkan kepada kalian. Maka jika raja itu teliti dalam
melaksanakan perintah untuk menjaga seluruh hamba dan balanya, maka raja ini akan
mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat sebab dari ia menjaga hamba Allah dan apa
yang telah diperbuat oleh Allah ta’ala kepada para raja yang berasal dari seluruh hamba
yang buruk.
Pemimpin dalam pandangan Kyai Ageng Imam Puro sebenarnya adalah pilihan Allah SWT,
bukan hanya pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan
oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan
dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada
perbuatan dosa, kemaksiatan dan kedzaliman. Hal ini telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah
manusia. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada
pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu
yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat
yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Dalam naskah manuskrip Kyai Ageng Imam Puro
halaman 54 dijelaskan :
Lan sebab dene kareksane artane Allah kang den serahake marang para ratu iku kabeh
apatah dene marang kawula balane maka dadya luwih luhur luwih mulya darajate saking
sakehe wong iku kabeh, lan sinungan kanugrahan. Lamun ana wong iku cilik maka orana
wong iku kabeh oleh kabecikan ora oleh kabecikan saking lobane lan ora eling saking
sakehe barang penggaweyane saking bangete bodhone khale ora pantes parentahe lan
penggaweane patrape marang sakehe kawulaning Allah lan marang sakehe arta kang ana
para ratu kabeh maka dadya lebur luwih eling ora karuan maka dadya kalakuane ratu iku
dadi ina lan wuwuh alane lan kaya mangkono upamane anane ratu kaya upamane wong
sawiji kang ginadhekaken dening ratu dinadekaken gedhe anduweni sasigar nagara. Lamun
ora becik penggaweane lan parentahe maka akhir-akhire dadya rusak. Lan tatkala sira
kawruhe martabate karaton ing sakehe para ratu kang wus kasebut ngarep iku menggah
bab pratingkahe kaagungan lan kabecikan ingdalem penggawean kang ana sajerone
karaton maka pahirsaken malih denira ing pasal kang teka buri iki amihasaken ing
sawirasatae ajar iki.
Sebab dijaga oleh Allah yang diserahkan oleh raja berserta pengikutnya maka menjadi lebih
luhur dan mulia derajatnya dari semua orang dan selalu dalam anugrah. Jika ada orang kecil
dalam tanggung jawabnya tidak ada kebaikan dalam pekerjaan seorang pemimpin karena
kebodohannya dan tidak pantas perintah dan pekerjannya terhadap semua makhluknya Allah
dan semua uang yang ada dalam penguasaan raja maka menjadi lebur dan sia-sia maka
56
menjadi raja yang hina dan buah kesalahannya dan seperti itu perumpamaan seseorang yang
dijadikan raja yang diberikan sebagian negara. Jika tidak baik pekerjaannya dan perintahnya
maka pada akhirnya akan menjadi rusak. Saat kamu mengetahui martabat keraton dari
semua raja yang sudah disebutkan didepan bahwa bab perilaku, keagungan dan kebaikan
didalam pekerjaan yang ada dalam keraton maka perhatikan kembali dalam pasal atau
pembahasan sebelum dan selanjutnya yang akn di sampaikan.
Maju mundurnya bangsa banyak ditentukan oleh para pemimpin. Sebab pada hakikatnya
pemimpin itu memiliki tanggungjawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.
Tanggungjawab inilah yang pada dasarnya terkait dengan moral kepemimpinan yang menjadi
anugrah. Kehidupan keseharianpun juga tidak lepas dari bagaimana seseorang melakukan
kepemimpinan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Pemimpin yang efektif adalah
pemimpin yang memiliki integritas dalam masalah uang. Banyak pemimpin-pemimpin yang sangat
handal jatuh karena melanggar integritas mereka dalam masalah uang. Peringatan kepada orang-
orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak
tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita
segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam
kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai
dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
B. Kitab Adāb al-Mulūk (Karatkter Ideal Pemimpin)
Kualitas kepribadian pemimpin yang ideal penting seyogyanya dimilliki oleh seorang
pemimpin. Seorang pemimpin juga harus mampu merangkul anggota atau bawahannya dari semua
lini tanpa membedakan fungsi dan posisi masing-masing. Di samping itu, pemimpin juga harus
mampu mengarahkan anggota dan bawahannya. Artinya pemimpin harus mampu mengarahkan,
menyemangati, dan mendorong agar memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja, yang
masih belum optimal dalam bekerja, bahkan yang masih malas. Terakhir, seorang pemimpin tidak
diharapkan untuk “overconfidence” dalam melakoni sikap kepemimpinannya. Sikap
“overconfidence” dapat menjerumuskan pemimpin kepada perilaku lalai atau lengah. Sikap lalai
atau lengahnya seorang pemimpin ini karena sikap “overconfidence” tersebut akan berakibat pada
gagalnya rencana yang telah disusun matang dan dapat berujung pada tujuan yang tidak sesuai
dengan yang diharapkan/targetkan.5
Kualitas kepribadian yang dapat menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang ideal dalam
manuskrip Kyai Ageng Imam Puro dicirikan dalam 10 (sepuluh) karakter yang ideal berikut ini ,
yaitu:
5 Sahadi dkk, “Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi” MODERAT Volume 6 Nomor 3 (Agustus)
2020. 519
57
Dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro pemimpin yang baik akan memainkan peran
kepemimpinan dengan menjadikan intelektual sebagai alatnya dan moral sebagai tuannya, jadi
intelektual harus dapat melayani moral. Bahkan, Einstein berabad-abad yang lalu pernah
mengemukakan bahwa manusia harus berhati-hati agar tidak mendewakan intelektual walaupun
intelektual memiliki daya kekuatan yang dahsyat, tetapi intelektual tidak mempunyai kepribadian.
Intelektual tidak dapat memimpin karena intelektual hanya dapat melayani.6 Kepemimpinan adalah
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dirinya maupun orang lain, sehingga kepemimpinan
adalah potensi yang melekat pada jati diri manusia. Berikut 10 (sepuluh) karakter yang ideal
seorang pemimpin dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro :
1. Berakal Sehat dan Berbudi Syariat
Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab
perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh
sebab itu, Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh semua
lapisan masyarakat. Pemimpin harus mampu mengembalikan umat kepada ketentuan-ketentuan
yang dibawa oleh Rasul, karena salah satu tugas pemimpin adalah sebagai pengganti tugas kenabian
dalam menjaga agama. Apabila pemimpin telah menentukan suatu peraturan, maka rakyat wajib
menaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan
Rasul-Nya.7
2. Berilmu/ Cerdas : Fathanah
Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehinga
memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala
macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi
menghadapai masalah, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin
yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk
menyelesaikan masalah tepat waktu. Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan
yang tinggii Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas
roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya
dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga
pencipta.8
Ketika seseorang telah memiliki ilmu yang mencukupi, kemudian dia menjadi pemimpin,
maka dia bisa memimpin dengan lebih baik daripada orang yang menjadi pemimpin tanpa memiliki
ilmu yang mencukupi. Karena salah satu power yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ilmu.
6 Jamal Mahdi, Menjadi Pemimpin Yang Efektif &Berpengaruh (Bandung: Syamil, 2001), 2
7 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 93
8 Murtadha Muthahhari, Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1995), 67
58
Hal ini telah dijelaskan di dalam ilmu kepemimpinan, ketika seorang pemimpin memiliki ilmu yang
banyak dan melebihi bawahannya, maka secara psikologis bawahnya akan lebih menghormatinya
dan mentaatinya.9 Dengan ilmu itu juga seorang pemimpin bisa memimpin dengan lebih baik dan
lebihtepat, sehingga dia bisa mengusahakan kemajuan dan kesuksesan bagi semua yang
dipimpinnya.
Jika ada seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu atau bodoh, maka dia akan kesulitan
untuk dapat memahami segala permasalahan negara atau lembaga yang dipimpinnya dan dia juga
akan kesulitan untuk mendapatkan respek dan ketaatan dari bawahannya. Oleh karena itu, ilmu
adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, terutama ilmu agama bagi pemimpin
agama, ilmu pemerintahan bagi pemimpin pemerintahan, dan ilmu manajemen serta kepemimpinan
secara umum bagi semua pemimpin.
3. Akil Balig
Seorang pemimpin haruslah seorang yang memenuhi syarat taklif, artinya dapat dibebani
hukum. Kriteria seorang yang dapat dibebani hukum tersebut yaitu sudah dewasa (baligh) dan
berakal sehat. Rata-rata yang menjadi pemimpin agama adalah mereka yang telah berusia dewasa
karena di usia ini telah terlihat kematangan spiritual dan moral sehingga memungkinkan bagi
seseorang untuk menjadi figur pemimpin agama. Kematangan beragama sendiri adalah
kemampuan seseorang dalam mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai
luhurnya yang kemudian direalisasikan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tingkah laku sehari-
hari. Ia menganut suatu agama dengan keyakinan bahwa agama tersebutlah yang terbaik sehingga ia
akan berusaha menjadi penganut yang baik. Dan keyakinan itu akan ditampilkan dalam sikap dan
tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketataannya pada agama.10
4. Budi Pekerti Baik
Budi pekerti/ akhlak merupakan perpaduan dari rasio dan rasa yang dimanifestasikan atau
diwujudkan dalam karsa dan tingkah laku manusia sehari-hari dalam kehidupan organisasi. Kata
hati sangat berperan dalam budi pekerti/ akhlak, namun demikian Ia tidak timbul dengan sendirinya,
tetapi perlu dibangun melalui strategi manajerial seorang pemimpin agar menjadi budaya organisasi
yang kuat untuk mencapai prestasi organisasi di masa mendatang. Implementasi manajerial
pemimpin dalam membangun budi pekerti/ akhlak dapat diadopsi dengan mempertimbangkan
situasi dan kondisi organisasi.11
9 Fazalur Rahman, Nabi Muhammad saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer, terj. Annas Siddik, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1991), 68 10
Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 109 11
Mumuh Muhtarom, Implementasi Kepemimpinan Dan Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan, DIKLAT
KEAGAMAAN Volume 12 Nomor 33 (Mei-Agustus) 2018. 152
59
Kesungguhan setiap pemimpin organisasi yang didukung oleh stakeholdes yang ada sangat
menopang keberhasilan dalam membangun budi pekerti/ akhlak yang terbaik dalam jangka panjang.
Hasil-hasilnya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan budaya organisasi dalam rangka mencapai
prestasi organisasi terbaik di masa mendatang. Setiap pemimpin yang hendak membangun budi
pekerti/akhlak yang luhur bagi stakeholders-nya perlu memahmi dan merumuskan konsep-konsep
ideal sesuai dengan harapan sebagaimana terimplisitkan dalam rumusan visi dan misi organisasi.
Pemimpin dapat menerapkan strategi manajerial dalam membangun budi pekerti/akhlak secara
dinamis, konsisten, dan melibatkan stkeholders organisasi. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara
baik, bangunan budi pekerti/akhlak akan kuat nan indah hingga dapat menghasilkan budaya
organisasi yang sesuai dengan harapan.
5. Peduli : Empati
Yang dimaksud dengan berempati dengan penderitaan rakyat adalah merasakan apa yang
dirasakan oleh rakyat. Bukan hanya bersimpati. Pemimpin yang memiliki rasa empati tinggi akan
memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia mencintai rakyatnya,
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika seorang pemimpin suka melakukan tindakan yang
melukai rakyatnya, sementara ia juga merasakan luka yang sama ketika diperlakukan seperti itu,
menurut Imam Ghazali, pemimpin yang demikian termasuk kategori pemimpin khianat yang tertipu
oleh kekuasaan.12
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu
mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga
memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi
pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan
pengawasan. Dengan bimbingan dan pengarahan, koordiansi dan pengawasan, pemimpin berusaha
mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap unit atau perseorangan dalam melaksanakan
volume dan beban kerjanya atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara
mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan kepentingan bersama.13
6. Welas Asih
Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri sendiri. Kepemimpinan menuntut
suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan sejati dimulai dari dalam
dan kemudian bergerak ke luar untuk melayani mereka yang dipimpinnya (al-Imamu Khodimul
Ummah). Disinilah pentingnya karakter dan integritas seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin
12
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan (Bandung: Mizan,
2010), 157 13
Evy Sumiati, Hubungan antara Empati Kepemimpinan dan Pengetahuan Terhadap Tugas dengan
Kemampuan Melaksanakan Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Sekolah di Taman Kanak-kanak Bengkulu,
MANAJEMEN PENDIDIKAN 2009, Volume.3 Nomor 4, 45
60
sejati dan diterima oleh rakyat yang dipimpinnya. Paling tidak menurut Ken Blanchard dan kawan-
kawan, ada sejumlah ciri dan nilai yang muncul dari seorang pemimpin yang memiliki hati yang
melayani, yaitu:14
a. Tujuan paling utama seorang pemimpin adalah melayani kepentingan mereka yang
dipimpinnya. Orientasinya adalah bukan untuk kepentingan diri pribadi maupun
golongannya, tetapi justru kepentingan publik yang dipimpinnya.
b. Seorang pemimpin sejati justru memiliki kerinduan untuk membangun dan mengembangkan
mereka yang dipimpinnya, sehingga tumbuh banyak pemimpin dalam kelompoknya.
7. Berani
Menjadi seorang pemimpin yang berani, terdengar cukup mudah tetapi pada kenyataannya
merupakan hal yang sulit untuk dilakukan setiap orang bisa menjadi seorang pemberani, tetapi
menjadi pemimpin yang pemberani adalah hal yang bisa dikatakan berbeda, karena besarnya
tanggung jawab dan tugas yang dihadapi oleh seorang pemimpin ini. Bahwa keberanian ini adalah
sifat berani menanggung resiko dari sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat
dan tepat waktu. Mengambil keputusan bukanlah hal mudah karena dibutuhkan keberanian, ada
lanjutannya dimana dijelaskan bahwa keberanian ini bukanlah bawaan sejak lahir tetapi bisa dilatih
dan dibentuk sehingga seorang yang akan menjadi pemimpin bisa dilatih supaya memiliki
keberanian.15
Dalam Islam keberanian ini disebut dengan istilah syaja’ah, yaitu ketetapan hati yang berani
untuk berupaya melangkah maju, atau mundur untuk mengatur kembali langkah-langkah
perjuangan. Ada dua macam syaja’ah, yaitu syaja’ah batiniyah (moralitas) atau syaja’ah adabiyah
dan syaja’ah jasmaniyah (fisik).16
Syaja’ah batiniyah, ialah keberanian mengatakan kebenaran dan
memberantas kebathilan, termasuk di dalamnya keberanian berbicara dan mengambil tindakan
untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan seseorang. Pemimpin yang memiliki keberanian
tersebut adalah pemimpin yang berwatak satria. Tujuannya, bukan untuk mencari popularitas atau
mendapatkan suatu jabatan, tetapi agar kebenaran menjadi pijakan yang kuat bagi setiap orang.
Syaja’ah jasmaniah (fisik), adalah kebenaran melalui kekuatan fisik. Keberanian untuk
mempertahankan diri, harta benda, dan keluarga, atau orang lain yang lemah, atau untuk membela
hak-hak masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia atau dari
bahaya alam. Sebagai pengemban kekuasaan, pemimpin dipersyaratkan bermoralitas tinggi,
pemimpin harus mampu memahami dan mengelola kekuasaan sebagai pemersatu masyarakat, agar
14
Jamal Mahdi, Menjadi Pemimpin Yang Efektif & Berpengaruh (Bandung: Syamil, 2001), 2 15
Sakdiah, Manajemen Oraganisasi Islam Suatu Pengantar (Banda Aceh : Dakwah Ar-Raniry Press, 2015),
115 16
Yayat Hidayat, Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia UPI,
2005) 26.
61
mereka saling menolong dalam memajukan mutu kehidupan seraya mempertahankan diri terhadap
berbagai macam ancaman. Memiliki moralitas yang tinggi, berpegang teguh kepada ajaran dan
kaidah agama, merupakan petunjuk dari adanya persyaratan untuk mengemban kekuasaan, di
samping keharusan adanya dukungan kelompok solidaritas yang cukup kuat. Sebaliknya, kehidupan
yang bergelimang kerendahan moral dan tidak mengindahkan ajaran dan kaidah agama atau budi
pekerti yang mulia, adalah tanda nihilnya persyaratan untuk mengemban kekuasaan.17
8. Mengurangi Makan dan Tidur
Para pemimpin pada zaman dahulu untuk menambah kekuatannya, mereka berani bertirakat
dengan berpuasa, mengurangi tidur, makan, dan minum. Tatkala rakyatnya tidur, pemimpinnya
justru berjaga, tatkala rakyatnya kenyang, mereka berani menahan lapar. Rupanya, di zaman modern
seperti sekarang ini yang banyak terjadi justru sebaliknya, yaitu rakyatnya lapar, pemimpinnya justru
kekenyangan dan bahkan hidup berlebih-lebihan. Pemimpijn yang demikian itu akan melahirkan
kehidupan masyarakat yang tidak stabil, kaya masalah, dan miskin makna dalam menjalani
kehidupan.18
Penggerak perilaku manusia berada pada hati. Maka, kekuatan untuk menghidupkan dan
menggerakkan juga berada pada hati yang tulus, bersih, dan sehat yang dimiliki oleh pemimpinnya.
Namun, pada akhir-akhir ini, tidak sedikit orang di dalam menjalankan kepemimpinan terlalu
mengedepankan akalnya. Bahkan, pendekatan transaksional pun dilakukan. Padahal, melalui cara
tersebut masalah yang sebenarnya tidak akan terselesaikan. Sebaliknya, melalui cara sederhana, yaitu
dengan hati yang tulus, bertanggung jawab, berintegritas, dan sanggup mencintai semuanya, maka
pemimpin akan berhasil menunaikan tugasnya, yaitu menghidupkan, menggerakkan, dan
mengarahkan mereka yang dipimpinnya.
9. Menahan Hawa Nafsu
Menghindari segala kezaliman, bagaimanapun bentuknya. Seorang pemimpin harus
memiliki sikap ini, dan menanamkannya dalam semua bawahannya, pembantu dan asistennya.
Seorang pemimpin harus mampu menjauhkan dirinya dan bawahannya dari segala perilaku yang
tidak pantas. Sekalipun ia bisa adil dan menjauh dari ketidakadilan, tetapi ternyata para
pembantunya dan pembantunya berbuat salah dan adil, ia akan diminta bertanggung jawab dan juga
akan menanggung dosa atas perilaku bawahannya yang zalim, sementara dia mendiamkannya.
Diantara contoh seorang pemimpin yang senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dan segenap
17
Zainuddin, A. Rahman, Pemikiran Politik Ibn Khaldun, Jurnal Ilmu Politik 10 (Jakarta : AIPI-LIPI
Gramedia, 1991), 78 18
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan
(Jakarta: Erlangga, 1980), 246
62
pembantunya dari sikap dzalim adalah Khalifah Umar bin Khaththāb ra. Khalifah Umar ra.
merupakan teladan ideal seorang pemimpin yang tidak rela dengan perilaku dzalim sekecil apa pun.
Beliau senantiasa mengingatkan para pembantunya agar berlaku adil dalam mengemban
amanah sebagai pelayan rakyat, sebagaimana yang tercermin dalam sebuah kisah, bahwa suatu
ketika, Khalifah Umar bin Khaththāb ra menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Asy’ari ra, yang
pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Bashrah dan Irak. Dalam suratnya, Khalifah Umar ra
berkata: “Ingatlah, sesungguhnya pemimpin yang paling sejahtera adalah yang mampu
menyejahterakan rakyatnya. Berhati-hatilah dengan sikap menyepelekan sesuatu, sebab para
pembantumu akan meniru perilakumu. Sesungguhnya engkau (yang sedang memegang kekuasaan)
laksana hewan ternak yang melihat padang hijau, lalu memakan rumput hingga banyak dan menjadi
gemuk. Gemuknya hewan ternaklah yang menyebabkannya menjadi binasa. Dan karena
kegemukannya itu, hewan ternak disembelih dan dimakan.”19
10. Pemimpin Laki-laki
Ketika Islam memberikan tanggungjawab berbeda, antara pria dan wanita tidak berarti Islam
meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Hak dan tanggung jawab itu sesungguhnya
didasarkan oleh perbedaan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah secara berbeda pula.
Allah dengan sifat al-Alim nya, tentulah lebih mengetahui apa yang baik dan bermanfaat bagi
kemaslahatan manusia dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Maka seorang muslim akan lebih
percaya kepada faliditas informasi dari Allah dan Rasul-Nya ketimbang mempercayai perasaannya
sendiri, sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa’: 34: “Kaum laki-laki itu pemimpin bagi
kaum perempuan, sebagaimana Allah telah melebhkannya atas kalian”. Rasulullah bersabda:
“…Dan wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai
pertanggungjawaban atasnya”. (HR. Bukhari dan Muslim). Abi Bakrah meriwayatkan sebuah
hadits: “Ketika sampai suatu berita kepada Rasulullah saw bahwa Bangsa Persia telah mengangkat
putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang
menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita”. (HR. Bukhari dan
Tirmidzi)20
Jika diteliti dari kesepuluh karakter kepemimpinan tersebut sebenarnya telah mencakup
semua macam karakter ideal pemimpin Islam-Jawa seperti seperti yang telah diuraikan di atas.
Dengan demikian, dapat diambil suatu pelajaran bahwa dengan menyadari adanya peranan-peranan
tersebut di atas kiranya sangatlah berguna bagi para pemimpin dan calon pemimpin atau lainnya
untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih berhati-hati untuk menuju ke arah yang lebih
baik lagi.
19
Hadari Nawawi, Hakekat Manusia Menurut Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 360-363 20
Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 72-75
63
C. Kitab Adāb al-Salāṭīn (Manajemen Kepemimpinan)
1. Manajemen Organisasi : Pemimpin Adil
Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata
manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti "mengendalikan", terutama
dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan".
Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki
arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Mary Parker Follet, misalnya mendefinisikan manajemen
sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang
manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky
W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan
efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien
berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain,
sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.21
Efisiensi ialah menghasilkan output sebanyak mungkin dari input sesedikit mungkin.
Efektivitas yaitu mengerjakan hal yang tepat atau menjalankan aktivitas-aktivitas secara langsung
yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Efisiensi lebih ke cara mencapai suatu
tujuan, sedangkan efektivitas lebih berkenaan dengan hasil atau pencapaian tujuan tersebut.
Pembahasan dalam manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan, yang meliputi perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengendalian (controlling).
Dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro pada salah satu bab Adāb al-Salāṭīn dijelaskan tentang
manajemen organisasi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.
Manajemen organisasi yang digagas oleh Kyai Ageng Imam Puro ini berorientasi kepada
pemimpin yang adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada 4 hal yang dilakukan
seorang pemimpin untuk mencapai status pemimpin yang adil dalam manuskrip Kyai Ageng Imam
Puro :
a. Beribadah kepada Allah SWT : Planning
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan berarti merupakan kegiatan menuntun, membimbing,
memandu untuk menunjukkan jalan yang diridai Allah SWT. Kegiatan itu bermaksud untuk
menumbuh kembangkan kemampuan mengerjakan sendiri di lingkungan orang-orang yang
dipimpin, dalam usahanya mencapai rida Allah SWT selama kehidupannya di dunia dan akhirat
21
Sarinah, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 3
64
kelak. Dengan kata lain, kepemimpinan Islam adalah kemampuan mewujudkan semua kehendak
Allah SWT yang telah diberitahukannya melalui Rasulnya serta dengan perencanaan yang baik.22
Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi, lembaga dan
kumpulan pendidikan lainya, tanpa adanya perencanaan maka jalannya organisasi tidak jelas arah
dan tujuannya. Oleh Karena itu perencanaan penting karena pertama, dengan adanya perencanaan
diharapan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Kedua, dengan perencanaan, maka dapat
dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Ketiga,
perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara terbaik atau
kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Keempat, dengan perencanaan dapat
dilakukan skala prioritas. Kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau
standar untuk mengadakan pengawasan.23
Dengan demikian perencanaan mempunyai peranan penting dalam organisasi umum maupun
dalam organisasi yang bersifat pribadi. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk
memprediksi kerja dimasa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil
yang akan dicapai. Dari penjelasan tersebut tergambar dengan jelas bahwa perencanaan dalam
manajemen organisasi sangat rumit. Dengan demikian perencanaan tidak dapat dilakukan tanpa
adanya pemikiran yang matang, komprehensif dan rasional. Untuk itu perhatian terhadap langkah-
langkah perencanaan dan segala yang berkaitan dengan perencanaan penting bagi manajemen dan
bagi para manajer.
b. Pengorganisasian : Organizing
Secara konsep, ada dua batasan yang perlu dikemukakan,yakni istilah “organizing” sebagai
kata benda dan “organizing” pengorganisasian sebagai kata kerja, menunjukan pada rangkaian
aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Istilah organisasi memiliki dua arti umum,
pertama, mengacu pada suatu lembaga (institution) atau kelompok fungsional, sebagai contoh kita
mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Arti
kedua mangacu pada proses pengorganisasian, sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Tujuan
pengorganisan adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab. Dengan pembagaian tugas diharapkan setiap organisasi dapat meningkatkan
keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan.24
22
Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktek (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 47-48 23
Abin Syamsuddin dkk, Perencanaan Pendidikan, (Bandung : Rosda Karya, 2007), 60 24
Paruhuman Tampubolon, Pengorganisasian Dan Kepemimpinan: Kajian Terhadap Fungsi-fungsi
Manajemen Organisasi Dalam Upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi, STINDO PROFESIONAL, Volume 4 Nomor
3 (Mei) 2018. 25
65
Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang
keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelesaian
pekerjaan itu. Tujuan organisasi dapat dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas. Hal ini penting
karena:25
a. Tanpa tujuan yang jelas organisasi tidak akan mempunyai arah.
b. Tanpa tujuan jelas, organisasi tida ada artinya dan hanya akan menimbulkan pemborosan
belaka.
c. Tujuan yang jelas akan mempermudah dalam membentuk dan struktur organisasi.
d. Tujuan yang jelas akan mempermudah dalam menentukan jumlah dan penempatan pegawai.
e. Tujuan yang jelas akan memberikan perangsang kerja pada para anggota organisasi.
f. Tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksanaan koordinasi, karena mereka menyadari
bahwa semua anggota organisasi bekerja ketujaun yang sama, yaitu tujuan organisasi.
g. Tujuan yang jelas merupakan awal dari penetapan strategi. Siasat, metode, dan prosedur
yang akan dipergunakan.
h. Tujuan yang jelas merupakan dasar dari pada organisasi untuk bergerak.
Ajaran Islam juga senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu
secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi
akan dengan mudah bisa diluluhlantakan oleh kebathilan yang tersusun rapi. Menurut Terry
pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh
sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
dengan sukses.
c. Ahli Puasa : Controling
Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam
pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak
terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan
pengawasan, ada tiga cara yang dilakukan Allah SWT:
a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri
Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai
dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa
Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang
dijalankan yakni sebagai berikut :
25
Ibid., 27
66
a. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)
b. Pengawasan masyarakat
c. Pengawasan Peradilan manajemen
Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama,
pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-
hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.26
Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan
tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan
mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
Pengawasan penting disebabkan karena Perubahan lingkungan organisasi, Peningkatan
kompleksitas organisasi, Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, Kebutuhan manager
untuk mendelegasikan wewenang, Komunikasi dan Menilai informasi dan mengambil tindakan
koreksi. Perancangan proses pengawasan diantaranya yaitu: Merumuskan hasil yang di inginkan,
Menetapkan penunjuk hasil, Menetapkan standar penunjuk dan hasil, Menetapkan jaringan
informasi dan umpan balik dan Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.27
Pengawasan dirasa sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena jika tidak ada
pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang
terjadi baik yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan
karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota
organisasi. Serta pengawasan dapat memicu terjadinya tindak pengoreksian yang tepat dalam
merumuskan suatu masalah. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin
organisasi. Disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu
organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan
organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi.
d. Berperang : Actuating
Pada dasarnya penggerakan sangat erat kaitannya dengan unsur manusia yang ada dalam
organisasi. Kegiatan organisasi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur manusia dapat
mendayagunakan seluruh unsur-unsur lainnya (non manusiawi) serta mampu melaksanakan tugas-
tugas yang telah ditetapkan. Penggerakan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan
pengorganisasian secara kongkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan
26
Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Rajawali Pers:
Jakarta, 2012), 180 27
Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), 133
67
yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Singkatnya actuating mencakup
kegiatan yang dilakukan seorang yang ditetapkan manager untuk mengawali dan melanjutkan
kegiatan yang telah di tetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan
dapat tercapai. Menggerakkan (Actuating) berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang
pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas manajemen. Arti penting sumber daya manusia
bagi suatu perusahaan terletak pada kemampuan untuk bereaksi secara sukarela dan secara positif
melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan.28
Dalam sejarah yang telah dibukukan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, ada beberapa langkah
yang dilakukan oleh para rasul atau sahabat dalam menggerakkan kaumnya, antara lain:29
a. Directing
Dalam memberikan arahan kepada bawahan, rasul telah memberikan
gambaran.Rasulullah dalam memerintah umatnya untuk melaksanakan sholat, rasul
memberikan contoh atau model. Di dalam Islam terdapat perintah atau kewajiban untuk
melaksanakan sholat dan haji, namun bagaimana melaksanakannya tidak dijelaskan secara
rinci, tapi disampaikan dalam bentuk contoh atau model yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam
sebuah organisasi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh elemen organisasi. Untuk
dapat melaksanakan aturan-aturan tersebut maka diperlukan tidak hanya arahan dalam bentuk
verbal maupun tulis, tetapi juga arahan dalam bentuk contoh prilaku oleh pemimpin.
b. Coordinating
Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maka musyawarah mutlak diperlukan.
Kegiatan pengorganisasian adalah sangat penting karena dengan hal ini akan bisa membawa
irama seluruh komponen organisasi berjalan sesuai dengan komando, standard operation of
procedure (SOP) organasasi, sehingga hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan kegiatan
dapat teratasi. Dengan adanya SOP tidak akan terjadi overlaping pekerjaan dan tanggungjawab,
apa dan kepada siapa seseorang atau departemen bertanggung jawab.
c. Communication
Dalam surat Al-Shafat: 102 dipaparkan bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk
menyembelih putranya, beliau tidak langsung melaksanakan perintah itu, akan tetapi terlebih
dahulu mengkomunikasikan perintah itu kepada putranya Nabi Ismail. Terkait dengan
komunikasi itu, di ayat yang lain dijelaskan,
28
Mochamad Nurcholiq, Actuating Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits (Kajian Al-Qur’an dan Al-
Hadits Tematik), EVALUASI. Vol.1, No. 2, (September) 2017. 140 29
Jawahir Tanthowi. Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur’an (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna,
1983), 75
68
“Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia
bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata-an)ku; sesungguhnya
aku khawatir mereka akan mendustakanku”.
Dari ayat ini terdapat tiga nilai, yaitu; Pertama, komunikasi; kisah di atas ketika Nabi
Musa diutus berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa mengalami hambatan berkomunikasi,
padahal hal itu sangat menentukan keberhasilan dakwah tersebut. Akhirnya Nabi Musa
mengutus Nabi Harus saudaranya untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun, karena dia
dipandang memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik.Sebaik apapun perencanaan dan
pengorganisasian suatu organisasi tidak akan berhasil tanpa proses komunikasi yang baik.
Selanjutnya, pendelegasian; kisah tersebut di atas juga bisa kita ambil ibrah bahwa dalam
melaksanakan tugas organisasi seorang pemimpin tidak harus melakukannya sendiri, akan
tetapi dapat mendelegasikan kepada bawahan yang mempunyai kompetensi yang lebih baik.
Yang terakhir, profesionalisme; bahwa pemilihan Nabi Harun untuk melaksanakan tugas
dakwah didasari atas prinsipprinsip profesionalisme, karena Nabi Harun memiliki kemampuan
yang lebih baik dalam komunikasi. Prinsip inilah yang seharusnya diterapkan dalam sebuah
organisasi dalam melaksanakan seluruh aktifitas keorganisasian.
d. Motivasi
Ketika rasulullah memimpin perang, Allah menyuruhnya untuk mengobarkan semangat
perjuangan bagi para mukminin. Rasul diperintah untuk memotivasi supaya pasukannya
bersemangat dalam peperangan. Motivasi mempunyai peran yang sangat penting. Seorang
pemimpin harus mampu membangkitkan motivasi bawahan dalam menjalankan tugas
organisasi. Seperti apa yang telah dilakukan Rasulullah ketika mengobarkan semangat juang
pasukannya dalam peperangan. Kalau mereka kalah pada peperangan itu akan mengakibatkan
kehancuran umat di dunia sampai akhirat. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai
tujuan sangat dipengaruhi oleh motivasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu
seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi.
2. Manajemen Kepemimpinan : Pemimpin Sukses
a. Berwibawa
Kewibawaan merupakan suatu hal sangat penting khususnya dalam kekuasaan, karena
menyangkut tentang suatu pembawaan serta keadilan. Kewibawaan sangat berpengaruh dalam
beberapa hal, baik itu dalam bernegara dan berorganisasi. Kewibawaan tidak hanya soal kekuasaan
negara, kewibawaan pun dibutuhkan dalam kekuasaan hukum. Negara pada hakikatnya merupakan
organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut
69
bangsa dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan sehingga negara dapat
memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut.30
Kekuasaan dalam arti kewibawaan diartikan bahwa pemegang kekuasaan memiliki sifat-
sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakatnya. Kewibawaan
ini tidak sama pada setiap pemegang kekuasaan. Pokok dalam melaksanakan kekuasaan adalah
apabila kekuasaan itu diterima oleh masyarakat dan dipatuhi. Kalau sudah dipatuhi maka segala
kekuasaan berubah menjadi kewibawaan, dengan pengertian bahwa rakyat yang menerima
kekuasaan yakin akan kebenaran dari kekuasaan itu. Untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan
cara yang paling efektif adalah dengan diadakannya suatu hukum.
Max Weber membagi kewibawaan menjadi tiga macam, yaitu pertama, Kewibawaan yang
bersifat kharismatik. Kewibawaan ini terdapat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat
kepribadian yang tinggi dan istimewa. Sebagai contoh kewibaan ini adalah kewibawaan para nabi-
nabi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengikut-pengikutnya atau kewibawaan seorang
presiden terhadap rakyatnya. Kedua, Kewibawaan yang bersifat tradisional. Kewibawaan ini
lazimnya dimiliki oleh seorang raja yang karena hak warisnya mempunyai pengaruh terhadap
rakyatnya. Keistimewaan pribadi seorang raja mungkin tidak ada atau mungkin juga ia tidak
sepandai seorang presiden, tapi karena hak wari yang dimilikinya itu rakyat patuh kepadanya dan ia
memiliki kewibawaan sebagai simbol dari kerajaannya. Ketiga, Kewibawaan yang bersifat rasional.
Kewibawaan ini didasarkan atas pertimbangan akal pikiran manusia yang banyak terdapat pada
organisasi-organisasi modern dengan disertai disiplin yang kuat dan birokrasi.31
Kewibawaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan tidak sama antara yang satu dengan
yang lainnya tergantung pada karakteristik kewibawaan itu. Untuk melaksanakan kekuasaan maka
seseorang atau beberapa orang tersebut harus memiliki legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan
berasal dari kata legitimate yang artinya authorized or sanctioned by conforming to law or rule.
Sedangkan dalam Dictionary of Law menyebutkan bahwa arti legitimate (adjective) adalah allowed
by law. Karena itu legitimasi kekuasaan akan berkaitan dengan 3 hal yakni:32
1) Sumber kekuasaan
2) Siapa pemegang kekuasaan
3) Bagaimana keabsahan dari kekuasaan tersebut.
b. Waspada
Arti yang lebih besar dari kepemimpinan adalah tindakan nyata, cara bekerja, dan
serangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kepemimpinan dapat dilihat kerangka pergerakan,
30
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 3 31
Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Setia Bandung: 2010), 198 32
Siswanto, Pengantar Manajemen (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2015), 158-159
70
perubahan, dan waktu. Jelasnya, tindakan kepemimpinan menurut Kyai Ageng Imam Puro ini
berbeda dari talking atau analyzing hal tersebut, media yang dipergunakan di sini akan menjadi
sesuatu yang penting untuk ditulis. Hal ini menjadi penting untuk memadukan apa yang terjadi
dalam kenyataan dengan teori haruslah menjadi keharusan, karena kepemimpinan menurut Kyai
Ageng Imam Puro ini tidak dinilai dari sudut pendekatan teoretis atau ideologi semata. Akan tetapi
kepemimpinan akan menghadapi suatu era perubahan pesat atau "accelerating" perubahan.
Karenanya, waktu merupakan faktor penting untuk menjadikan seorang pemimpin waspada.
Guna menghadapi perubahan pesat ini dengan baik, pemimpin harus memiliki serangkaian
kompetensi yang pokok seperti kemampuan antisipasi, kecepatan, agility dan persepsi. Antisipasi
berarti bahwa kepemimpinan harus secara proaktif mengamati lingkungan guna menemukan
perubahan yang secara negatif maupun positif mempengaruhi organisasi. Pemimpin harus secara
aktif mendukung pekerja untuk bersiap setiap saat menghadapi perubahan pesat lingkungan, dan
untuk mempertahankan pemimpin dan para manajer selalu menaruh perhatian atas hal tersebut.
Menjadi “perceptive, nimble dan innovative” dalam lingkungan yang berubah pesat akan
memberikan manfaat bagi organisasi. Sebagai tambahan, praktik menggunakan skenario “what if”
menguntungkan bagi para pemimpin.33
Secara rutin, mempertimbangkan dan mendiskusikan kemungkinan seluruh skenario yang
mungkin dapat terjadi pada masa depan, menjaga pemimpin harus waspada untuk memfokuskan
dan menyiapkan beragam kemungkinan. Penciptaan rencana-rencana darurat dapat berguna untuk
beberapa skenario. Pemimpin waspada melihat kecepatan sebagai sebuah kemampuan yang harus
dikuasai guna memuaskan konsumen yang menginginkan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan
seketika. Pelayanan yang cepat, bersahabat dan efisien merupakan contoh dari apa yang diinginkan
oleh pelanggan terhadap pelayanan pemerintah. Teknologi informasi, pelayanan on-line melalui
internet merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam membentuk highest quality service. Hal ini
menandakan, kecepatan pelayanan membantu pemerintah dalam meraih simpati dan kerja sama
warga.34
Perceptiveness merupakan kapasitas penting lain dari pemimpin waspada. Pemimpin harus
waspada terhadap segala bentuk intrik dan perubahan di lingkungan eksternal. Kewaspadaan ini
harus segera ditindaklanjuti guna merespon secara cepat dan tepat, dan mengambil langkah-langkah
yang tepat. Pada kasus dimana peluang dirasa ada, pemimpin harus segara bertindak. Leadtime juga
penting bagi kesuksesan organisasi karenanya, pemimpin waspada harus memiliki "radar screens"
yang selalu menyala setiap saat.
33
Hadari nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Gadja Madja University: Yogyakarta, 1996), 352 34
Vietsal Rivai, Islamic Leadership (Membangun Superleadersip Melalui Kecerdasan Spiritual) (PT Bumi
Aksara: Jakarta, 2013), 389
71
BAB V
RELEVANSI KEPEMIMPINAN PUBLIK
DALAM MANUSKRIP KYAI AGENG IMAM PURO
A. Potret Kepimpinan Publik Di Indonesia
Behn mengidentifikasi delapan tanggungjawab dari kepemimpinan sektor publik:
Pertama, berusaha untuk mencapai kepentingan umum. Kedua, identifikasi dengan jelas
keberhasilan dengan dengan melakukan benchmarking. Ketiga, mengembangkan strategi untuk
mencapai kesuksesan. Keempat, menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan.
Kelima, menekankan adanya rincian yang jelas dari pelaksanaan. Keenam, untuk mencapai
tujuan yang lebih luas pengaruh dengan memotivasi anggota dan stakeholders untuk
menciptakan lingkungan yang positif dengan konsensus. Ketujuh, mengenali dan
memanfaatkan keberuntungan mereka dan, ketika mereka tidak beruntung, tetap fokus pada
tujuan mereka publik dan meraba-raba jalan mereka ke arah itu. Kedelapan, membuat
organisasi lebih baik daripada itu.1
Kepemimpinan publik menciptakan koalisi internal dan eksternal untuk mendapatkan
dukungan atas tindakan mereka. Tindakan mereka harus mendukung kepentingan publik.
Sumber daya yang langka, sehingga para kepemimpinan publik harus mengikuti proses dan
prosedur organisasi serta ketentuan konstitusi dan peradilan dalam mengembangkan strategi.
Kepemimpin publik tidak bisa melanggar aturan organisasi mereka untuk mengejar keyakinan
mereka sendiri. Pemimpin badan publik seharusnya tidak hanya fokus pada tindakan
kewirausahaan untuk motif keuntungan, seperti Boone Pickens lakukan di Mesa Petroleum.
Profit motif bagi para pemangku kepentingan tidak dapat menjadi dasar untuk aksi dari
Pemimpin badan publik. Efektivitas kepemimpinan di sektor publik penting karena
menentukan kepuasan dan kepercayaan warga negara, dan reputasi organisasi. 2
Fokus pada teori-teori terbaru selalu menjadi bagian kritik dari teori sebelumnya dengan
mengabaikan pendekatan kepemimpinan klasik, seperti pendekatan sifat, perilaku, gaya, dan
situasional. Teori-teori ini dikritik karena perspektif terlalu sempit yang gagal dalam merespon
realitas kepemimpinan yang semakin kompleks. Pendekatan klasik berasumsi bahwa ada
pengaruh pribadi yang bersifat searah antara pemimpin ke pengikutnya. Pemimpin tradisional
memiliki kepribadian tertentu dengan sifat-sifat yang berbeda dari pengikutnya. Mereka
dikonseptualisasikan pemain aktif dalam proses kepemimpinan. Sebaliknya, para pengikut
1 Sarinah, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 3
2 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktek (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 47-48
72
dianggap sebagai pasif dan reaktif. Selain itu, hubungan kepemimpinan dalam konteks formal
hirarki biasanya dipahami sebagai situasi yang telah ditentukan secara sosial. Akibatnya yang
memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak.
Ada tiga argumen mengapa New Public Leadership yang memiliki arti penting dalam
konteks kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Komponen
kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam kebijakan pemerintah dalam
mendukung program modernisasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan
yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan publik memiliki potensi untuk menghasilkan
pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk
meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik.3
Ada tiga komponen utama dalam New Public Leadership yang melekat dalam konteks
reformasi sektor publik, yaitu: 4
1. Peran kepemimpinan
Momentum peningkatan dalam reformasi sektor publik pasca 1997, merupakan bagian
dari agenda pemerintah modernisasi yang lebih luas yang berusaha untuk memperkuat lebih
terbuka, transparan dan pemerintah berfokus pada pelanggan dengan maksud untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ketentuan pelayanan publik. Sejumlah tantangan
kepemimpinan kunci yang disajikan oleh kebanyakan program reformasi untuk organisasi
sektor publik. Pertama dan terpenting adalah bahwa berbagai program reformasi sedang
dilaksanakan dalam kolaboratif. Tantangannya menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan
adalah lebih penting daripada manajemen dalam mendorong berbagi belajar di lembaga-
lembaga sektor non-tradisional dan dalam lingkungan yang semakin jaringan.
2. Network Management
Manajemen jaringan semakin penting bagi tata kelola dan kepemimpinan dan
manajemen. Agranoff dan Mc Guire menyatakan bahwa manajemen jaringan menawarkan
kelas penting dari manajemen kolaboratif model. Pemahaman mereka berasal terutama dari
teoritis pemeriksaan, daripada empiris katalogisasi, tugasnya. mereka mencatat bagaimana
beberapa koleganya mengidentifikasi bagaimana manajer campur tangan dalam yang ada antar-
hubungan, mempromosikan interaksi, dan memobilisasi koordinasi dan dengan demikian
bekerja dalam jaringan. Jadi ada kebutuhan untuk mengamati saling ketergantungan fungsional
tapi ini bab berpendapat bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sering diabaikan
ketika memeriksa pentingnya kepemimpinan jaringan.
3 Hadari nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Gadja Madja University: Yogyakarta, 1996), 352
4 Abin Syamsuddin dkk, Perencanaan Pendidikan, (Bandung : Rosda Karya, 2007), 60
73
3. Nilai publik sebagai hasil dari kepemimpinan publik yang efektif
Nilai publik sebagai sebuah konsep pertama kali didukung oleh Mark Moore dan
kemudian diperluas di dalam konteks Inggris oleh Talbot dan Kelly dengan tujuan untuk
mengidentifikasi tujuan sosial, memberikan tujuan tersebut dengan cara yang
mempertahankan kepercayaan dan legitimasi dan memastikan bahwa organisasi sektor
publik memiliki kemampuan dan kapasitas untuk tujuan yang telah ditetapkan. Semua
pemimpin publik terlibat dalam pemahaman, menciptakan dan menunjukkan nilai publik.
Sebaliknya, fungsi administrasi publik tradisional baik di stabil lingkungan dengan tujuan
utama memberikan barang publik. 5
Dari konstruksi teori tentang kepemimpinan transformasional yang dipaparkan di
atas, jelas bahwa tipe kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan dan relevan
dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Kondisi masyarakat kita saat ini sedang krisis
kepercayaan (distrust), terjadi degradasi moral bangsa, dibuktikan dengan masih cukup
tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta etika berpolitik yang kurang baik
yang berakibat semakin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Presiden Joko Widodo sejak awal menjabat sudah bertekat melakukan revolusi mental, yang
artinya bahwa diperlukan suatu perubahan besar dalam pola pikir, perilaku, sikap dan mental
seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan suatu perubahan. Oleh sebab itu dibutuhkan
pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang
lebih baik, mampu membangun kepercayaan diri pengikutnya, mampu menjadi tauladan
bagi yang dipimpin, serta mampu mentransfer ide-ide perubahan kepada anggota organisasi
yang dipimpinnya sehingga mau melakukan kegiatan untuk mencapai visi tersebut. Untuk
itu pemimpin transformasional sangat relevan dan dibutuhkan dalam kondisi masyarakat dan
bangsa kita pada saat ini.
B. Karakter Pemimpin Sejati
Setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Dalam tulisan ini penulis
memperkenalkan sebuah jenis kepemimpinan yang sebut dengan Q Leader. Kepemimpinan Q
dalam hal ini memiliki empat makna. Pertama, Q berarti kecerdasan atau intelligence (seperti
dalam IQ-Kecerdasan Intelektual, EQ-Kecerdasan Emosional, dan SQ-Kecerdasan Spiritual). Q
Leader berarti seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan IQ-EQ-SQ yang cukup tinggi.
Kedua, Q Leader berarti kepemimpinan yang memiliki quality, baik dari aspek visioner
maupun aspek manajerial. Ketiga, Q Leader berarti seorang pemimpin yang memiliki qi
5 Paruhuman Tampubolon, Pengorganisasian Dan Kepemimpinan: Kajian Terhadap Fungsi-fungsi Manajemen
Organisasi Dalam Upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi, STINDO PROFESIONAL, Volume 4 Nomor 3 (Mei)
2018. 25
74
(dibaca “chi” bahasa Mandarin yang berarti energi kehidupan). Makna Q keempat adalah
seperti yang dipopulerkan oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai qolbu atau inner self.
Seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang sungguh-sungguh mengenali dirinya (qolbu-
nya) dan dapat mengelola dan mengendalikannya (self management atau qolbu management).6
Menjadi seorang pemimpin Q berarti menjadi seorang pemimpin yang selalu belajar
dan bertumbuh senantiasa untuk mencapai tingkat atau kadar Q (intelligence-quality-qi-qolbu)
yang lebih tinggi dalam upaya pencapaian misi dan tujuan organisasi maupun pencapaian
makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin. Kepemimpinan Q dapat dirangkum dalam
tiga aspek penting dan saya singkat menjadi 3C , yaitu: 7
1. Perubahan karakter dari dalam diri (character change)
2. Visi yang jelas (clear vision)
3. Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (competence)
Ketiga hal tersebut dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa
bertumbuh, belajar dan berkembang baik secara internal (pengembangan kemampuan
intrapersonal, kemampuan teknis, pengetahuan) maupun dalam hubungannya dengan orang lain
(pengembangan kemampuan interpersonal dan metoda kepemimpinan). Seperti yang dikatakan
oleh John Maxwell: 8
“ The only way that I can keep leading is to keep growing. The day I stop growing,
somebody else takes the leadership baton. That is the way it always it.”
Satu-satunya cara agar saya tetap menjadi pemimpin adalah saya harus senantiasa
bertumbuh. Ketika saya berhenti bertumbuh, orang lain akan mengambil alih
kepemimpinan tersebut.
Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat
yang dilekatkan kepada gambaran seorang pemimpin. Mitos ini disadari atau tidak
mempengaruhi pengembangan pemimpin dalam organisasi. Ada 3 (tiga) mitos yang
berkembang di masyarakat, yaitu :9
1. Mitos the Birthright
Berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan (dididik). Mitos ini
berbahaya bagi perkembangan regenerasi pemimpin karena yang dipandang pantas menjadi
pemimpin adalah orang yang memang dari sananya dilahirkan sebagai pemimpin, sehingga
yang bukan dilahirkan sebagai pemimpin tidak memiliki kesempatan menjadi pemimpin . Teori
Genetis (Keturunan). Inti dari teori menyatakan bahwa “Leader are born and nor made”
6 Vietsal Rivai, Islamic Leadership (Membangun Superleadersip Melalui Kecerdasan Spiritual) (PT Bumi
Aksara: Jakarta, 2013), 389 7 Ibid., 27
8 Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer (Rajawali Pers:
Jakarta, 2012), 180 9 Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), 133
75
(pemimpin itu dilahirkan (bakat) bukannya dibuat). Para penganut aliran teori ini
mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia
telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang
ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali kelak ia akan timbul
sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis pandangan ini tergolong pada
pandangan fasilitas atau determinitis.
2. The For All Seasons
Berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin selamanya dia akan menjadi
pemimpin yang berhasil. Pada kenyataannya keberhasilan seorang pemimpin pada satu situasi
dan kondisi tertentu belum tentu sama dengan situasi dan kondisi lainnya.
3. The Intensity
Berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerja itu
pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Pada kenyataannya
kekerasan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja hanya pada awal-awalnya saja,
produktivitas seterusnya tidak bisa dijamin. Kekerasan pada kenyataannya justru dapat
menumbuhkan keterpaksaan yang akan dapat menurunkan produktivitas kerja.
C. Kepemimpinan Publik Masa Depan
Visi dan Kompetensi Kepemimpinan Publik Masa Depan Dengan landasan penalaran
yang tajam, Brill dan Worth memberikan ramalan bahwa organisasi masa depan yang akan
mampu bersaing harus memiliki visi yang jelas dan terarah. Visi adalah suatu pernyataan yang
berisi arahan yang jelas tentang apa yang harus diperbuat organisasi di masa yang akan datang.
“A vision is a realistic, credible, attractive future for your organization”. Visi yang jelas dan
tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi akan mampu menumbuhkan hal-hal berikut: 10
1. Menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan mampu memupuk semangat
kerja karyawan.
2. Menumbuhkan rasa kebermaknaan di dalam kehidupan kerja karyawan.
3. Menumbuhkan standar kerja yang prima.
4. Menjembatani keadaan organisasi masa sekarang dan masa depan.
Penelitian Collin dan Porras menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki visi dapat
melampaui prestasi organisasi yang tidak memiliki visi sampai 55 kali.11
Suatu survai yang
dilaksanakan majalah Fortune terhadap 1500 pimpinan senior perusahaan, mengungkapkan
ciri-ciri atau kemampuan paling dominan yang harus dimiliki pimpinan pada tahun 2000 adalah
10
Jawahir Tanthowi. Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur’an (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna,
1983), 75 11
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), 3
76
kemampuan merumuskan visi masa depan. Menurut Kotter visi organisasi merupakan tanggung
jawab pemimpin organisasi. Visi adalah komponen sentral dari kepemimpinan yang hebat
(great leadership). Dengan visinya seorang pemimpin memberikan jaminan
kepastian/keamanan kepada anak buahnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan karena
pengaruh perubahan lingkungan. Sudah jelas bahwa pekerjaan yang tidak ringan dan menjadi
keharusan bagi seorang pemimpin untuk dapat merumuskan visi kepemimpinannya (visi
organisasi) dengan jelas dan terarah.
Untuk dapat merumuskan visi yang jelas, kepemimpinan organisasi harus
mempertanyakan hal-hal berikut apa visi dan tujuan organisasi saat ini, apa manfaat organisasi
bagi masyarakat, apa ciri wilayah kerja dan kerangka kerja institusional dimana organisasi
beroperasi, apa keunikan organisasi di dalam wilayah garapan atau di dalam struktur yang
dimasuki, dan hal-hal apa yang harus dilakukan agar organisasi maju dan berkembang. Di
depan telah disodorkan kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin yang terangkum
dalam 5 dimensi.12
Mendasarkan pada fenomena perubahan yang terus menerus terjadi, di
samping harus memiliki visi yang jelas dan terarah, pemimpin organisasi masa depan harus
memiliki kompetensi yang menonjol sesuai lingkungan perubahan. Spencer mengidentifikasi
beberapa kompetensi yang akan semakin penting bagi pemimpin organisasi masa depan yang
meliputi: 13
1. kemampuan berpikir strategis, yaitu kemampuan untuk memahami kecenderungan perubahan
lingkungan yang berlangsung cepat, peluang pasar, ancaman kompetisi, kekuatan dan
kelemahan organisasi yang dipimpinnya, serta mampu mengidentifikasi tanggapan-tanggapan
strategis.
2. Kepemimpinan dalam perubahan, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan visi strategis
organisasi kepada seluruh pihak yang terkait, menciptakan komitmen dan motivasi, penggerak
inovasi dan semangat kewirausahaan, serta mampu mengalokasikan sumber daya organisasi
secara optimal untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi.
3. pengelolaan hubungan, yaitu kemampuan untuk membina hubungan di tengah-tengah jaringan
kerja yang kompleks, baik dengan partner usaha maupun pihak lain yang memiliki pengaruh
terhadap keberlangsungan organisasi.
12
Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen (Pustaka Setia Bandung: 2010), 198 13
Siswanto, Pengantar Manajemen (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2015), 158-159
78
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian teori, analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
1. Kyai Ageng Imam Puro merupakan seorang ulama Ponorogo yang punya kredibilitas tinggi dan
wawasan yang luas, ditambah lagi dengan konteks sosial politik nusantara waktu itu dan
dengan latar belakang dan sejarah penulisan yang kompleks akan sangat menarik untuk dibahas
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro ini. Jika dilihat dari isinya, Manuskrip Kyai Ageng Imam
Puro ini cukup tebal karena terdapat 82 halaman serta mempunyai keistimewaan yang luar
biasa dalam mengulas masalah kepemimpinan diantaranya pertama, dari sisi sajian redaksi
kalimatnya yang kental nuansa sastra. Kedua, referensi naskah yang autentik. Ketiga,
kontekstualisasi dengan kondisi keindonesiaan khususnya Jawa. Seharusnya pemikiran Kyai
Ageng Imam Puro ini masih sangat layak dan penting untuk menjadi referensi atau acuan bagi
orang Jawa ketika mengkaji hal yang berkaitan dengan permasalahan kepemimpinan.
2. Dalam menguraikan kepemimpinan Islam-Jawa Kyai Ageng Imam Puro ditulis menjadi 2 bab
pertama, bab Kitāb Naṣāiḥ al-Mulūk (Integritas Moral Pemimpin) berisi tentang kepemimpin
adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam
upaya mencapai tujuan organisasi. Kedua, Kitab Adāb al-Mulūk (Karatkter Ideal Pemimpin)
inti bab ini adalah kualitas kepribadian pemimpin merupakan hal yang paling ideal dan penting
dimilliki oleh seorang pemimpin. Terdapat 10 kriteria seorang pemimpin menurut Kyai Ageng
Imam Puro antara lain : Berakal Sehat dan Berbudi Syariat, Berilmu/ Cerdas : Fathanah, Akil
Balig, Budi Pekerti Baik, Peduli : Empati, Welas Asih, Berani, Mengurangi Makan dan Tidur,
Menahan Hawa Nafsu, Pemimpin Laki-laki.
3. Dibutuhkan pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin transformasional,
Kepemimpinan transformasional memiliki visi kolektif jelas, memiliki kemampuan
mengkomunikasikan secara efektif terhadap seluruh pegawai, melalui berbagai cara, antara lain
memberi contoh yang memberi inspirasi bahwa kepentingan organisasi lebih dari kepentingan
individual. Dalam kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan,
kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk
melakukan pekearjaan lebih produktif dari yang direncanakan diawal.
79
B. Rekomendasi
Manuskrip Kyai Ageng Imam Puro sebagai karya sastra warisan budaya Nusantara secara
umum dan khususnya membahas kepemimpinan Islam-Jawa, juga banyak memuat konsep
kepemimpinan Islam-Jawa. Ini memungkinkan kajian yang lebih beragam dari varian tema yang
dimuat dalam manuskrip Kyai Ageng Imam Puro. Sebuah kesadaran apresiatif yang diwujudkan
dengan telaah kritis atas hasil budaya masa lalu ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan
determinatif masa kini dan konstruksi wacana antisipatif masa depan.
80
DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah, Chaedar. Filsafat Bahasa Dan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014
Anwar, Saifuddin Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001
Ardana, Komang. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
As-Sadlan, Shalih Bin Ghanim. Aplikasi Syariat Islam. Jakarta : Darul Fallah, 2002
Baharuddin. Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktek. Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012
Baidan, Nasharuddin. Etika islam dalam Berbisnis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
Baried, Siti Baroroh. Pengantar Teori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
Bungin, Burhan Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
Covey, Stephen R Principle-Centered Leadership. New York: Simon & Schuster, 1992
Dharma, Agus Gaya kepemimpinan yang Efektif bagi Para Manajer. Bandung: Sinar Baru, 1984
Effendi, Usman Asas Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo,2011
Endraswara, Suwardi. Falsafah Kepemimpinan Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2013
Fakih, Mansur. Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
Geertz, Cliford. The Religion of Java. New York: Free Press, 1964
Hurlock, Elizabeth B. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan.
Jakarta: Erlangga, 1980
Ibrahim, Ahmad. Manajemen Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006
Jaelani, Abdul Qadir. Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1995
Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
Kartakusumah, Berliana Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer. Jakarta: PT
Mizan Publika, 2006
Kartakusumah, Berliana. Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer. Jakarta: PT
Mizan Publika, 2006
Lorens, Bagus Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
Lubis, Nabilah. Naskah, Teks, & Metode Penelitian Filologi. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan
Depag RI, 2007
Mahdi, Jamal Menjadi Pemimpin Yang Efektif & Berpengaruh. Bandung: Syamil, 2001
Mahdi, Jamal. Menjadi Pemimpin Yang Efektif &Berpengaruh. Bandung: Syamil, 2001
Marsetio. Kepemimpinan Nusantara Archipelago Leadership. Bogor: Univ. Pertahanan, 2018
Martoyo, Susilo. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE, 2000
MoleongLexy J. Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
Muhtarom, Mumuh Implementasi Kepemimpinan Dan Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan,
DIKLAT KEAGAMAAN Volume 12 Nomor 33 (Mei-Agustus) 2018
Mulyono, Hardi. “Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Perguruan Tinggi” Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3. No. 1 2018
Mustaqim, Abdul Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKiS, 2010
Muthahhari, Murtadha Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Cet. I. Bandung: Mizan, 1995
Nawawi, Hadari. Hakekat Manusia Menurut Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
Nawawi, Hadari. Kepemimpinan Menurut Islam. Yokyakarta: Gajah Mada Unuversiuty Press, 2001
Nurcholiq, Mochamad. Actuating Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits (Kajian Al-Qur’an
dan Al-Hadits Tematik), EVALUASI. Vol.1, No. 2, (September) 2017
Prastowo, Andi Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. ArRuzz
Media, Jogjakarta, 2016
Purwowijoyo. Babad Ponorogo Jilid III: R. Brotodiningrat. Ponorogo: Depdikbud, 1985
Purwowijoyo. Babad Ponorogo Jilid V: Desa Perdikan. Ponorogo: Depdikbud, 1985
Purwowijoyo/ Babad Kandha Wahana: 19 Desa Kecamatan Ponorogo,. Ponorogo: Dep.
Pendidikan dan Kebudayaan Ponorogo, 1990
81
Rahman, Dani Nur “Peran Kepemimpinan Jawa” Diponegoro Journal Of Management, Vol. 1 No.
1 2012
Rahman, Fazlur Islamic Methodology in History, Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1946
Rahman, Fazlur Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer. Jakarta: Bumi Aksara, 1991
Rahman,Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, Chicago &
London: The university of Chicago Press, 1982
Ritzer, George Teori Sosiologi Modern, Terj. Alimandan, Jakarta: Prenada media, 2005
Rivai, Veithzal. Kiat Kepemimpinan dalam Abat-21. Jakarta: Murai Kencana, 2004
Rivai, Vietzal. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta; PT Raja Grafindo
Persada, 2013
Rosyadi, Khoirul. Mistik Politik Gus Dur. Yogyakarta: Jendela, 2014
Sahadi. “Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi” MODERAT Volume 6 Nomor 3
(Agustus) 2020
Sakdiah. Manajemen Oraganisasi Islam Suatu Pengantar. Banda Aceh : Dakwah Ar-Raniry Press,
2015
Shodieq. Pulungku. Ponorogo:Nirbita, 1984
Sofyan, Harahap. Etika Bisnis Dalam Perspektif islam, Jakarta; Salemba Empat, 2011
Sugianto, Alip Eksotika Pariwisata Ponorogo. Yogyakarta: Samudra Biru, 2015
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta, 2011
Sumiati, Evy. Hubungan antara Empati Kepemimpinan dan Pengetahuan Terhadap Tugas dengan
Kemampuan Melaksanakan Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Sekolah di Taman
Kanak-kanak Bengkulu, MANAJEMEN PENDIDIKAN 2009, Volume.3 Nomor 4
Sutikno, M. Sobry Pemimpin dan Kepemimpinan. Lombok: Holistica, 2014), 15
Suyami, Konsep Kepemimpinan Jawa Dalam Ajaran Sastra Cetha Dan Astha Brata. Yogyakarta:
Kepel Press, 2008
Tampubolon, Paruhuman Pengorganisasian Dan Kepemimpinan: Kajian Terhadap Fungsi-fungsi
Manajemen Organisasi Dalam Upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi, STINDO
PROFESIONAL, Volume 4 Nomor 3 (Mei) 2018
Tanjung, Hendri. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2003
Tanthowi, Jawahir. Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur’an. Jakarta
Tim Penulis, Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Pemda Ponorogo, 1996
Toto, Tasmara. Spiritual Centered Leadership. Jakarta : Erlangga, 2005
Wahid, Ramli Abdul. Ulumul Qur’an, Ed. Rev, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
Wahyudi, Sarjana Sigit. “Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam Dalam Masyarakat Jawa” Sabda
Vol. 6 No. 1 April 2021
Wahyudin, Ade Herlan “Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita Dan Fakta”, AN-NIDHOM
Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016
Woodward, Mark R. Islam Jawa Kesalehan Normatif . Yogyakarta: LKiS, 2004
Yahya, Yohannes Pengantar Manajemen. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
Zainal,Veithzal Rival Islamic Manajemen. Yogyakarta: BPEE, 2013
Zakub, Hamzah. Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan. Bandung: CV
Diponegoro. 2008
BIOGRAFI PENULIS
Heru Budi Suseno dilahirkan pada tanggal 22
November 1996 di Ponorogo, putra pertama dari Bapak
Lasimun dan Ibu Supatmi serta adik pertama Hery Prayitno
dan adik kedua Alif Thoriqul Huda. Pendidikan sekolah
dasar ditempuh di SDN 1 Sukosari Babadan Ponorogo
tamat pada tahun 2008. Pendidikan berikutnya dijalani di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Ponorogo dan tamat pada tahun 2011.
Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2
Ponorogo dengan mengambil jurusan Agama dan tamat pada tahun 2014. Pada
tahun 2015 melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir tamat tahun 2019. Setelah
itu melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo dengan mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam.
Sebelum dan sesudah menyelesaikan pendidikan sarjana dan
pascasarjananya banyak pengalaman bekerja di dunia pendidikan antara lain:
Madrasah Diniyah Nurus Salam Sukosari sebagai ustadz al-Qur’an, SMPN 1
Kauman sebagai pengajar Tahfidz al-Qur’an sejak tahun 2017-2020, SMK PGRI
Somoroto sebagai pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sejak tahun
2020-2022, SDN 1 Sukosari sebagai pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi
Pekerti sejak tahun 2021-sekarang. Dalam bidang organisasi banyak pengalaman
yang dicapainya antara lain: Pengurus forum mahasiswa Tafsir-Hadis nasional
yang tergabung dalam FKMTHI Nasional divisi intelektual tahun 2018-2022,
pengurus karang taruna kabupaten Ponorogo tahun 2019-2023.