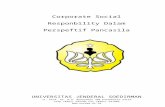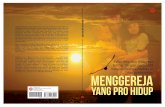KETELADANAN PERSPEKTIF HAMKA KAJIAN TAFSIR AL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KETELADANAN PERSPEKTIF HAMKA KAJIAN TAFSIR AL
KETELADANAN PERSPEKTIF HAMKA KAJIAN TAFSIR AL-
AZHAR
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Oleh:
Munajat
NIM. 11140340000214
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1442 H /2021 M
dc
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
Skripsi yang berjudul KETELADANAN PERSPEKTIF HAMKA KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 06 juli 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
Jakarta, 11 Agustus 2021
Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. Eva Nugraha, M.A
Aktobi Ghozali, MA NIP. 19710217199802 1 002 NIP. 19730520 200501 1 003
Anggota,
Penguji I, Penguji II,
Drs. Ahmad Rifqi Muchtar, M.A
Hasanuddin Sinaga, M.A. NIP. 19690822 199703 1 002 NIP. 19701115 199703 1 002
Pembimbing,
Dr. Suryadinata, MA NIP. 19600908 198903 1 005
VT
vii
ABSTRAK
Munajat, NIM 11140340000214
“Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir al-’Azhar”
Kajian ini mengenai suatu hal tindakan perilaku seseorang, yang
mencontohkan sifat baik dalam suatu bermasyarakat tentu bagi generasi
muda seperti remaja dalam bergaul terhadap teman sebayanya ataupun orang
yang lebih dewasa umurnya. Terkadang remaja perlu tahu akan suatu sikap
yang baik ketika berinteraksi dengan orang dewasa. harus mencerminkan
sopan santun pada dirinya, agar orang dewasa tersebut dapat mengetahuinya
dengan tindakan yang dilakukan. Karena seseorang dapat memprediksi orang
yang baik dan buruk akan suatu sikap pada dirinya tersebut.
Penulis menyinggung pada suatu surah al-Aḥzāb Ayat 21 dan surah
al-Mumtaḥanah ayat 4 dan 6 dalam al-Qur‟an. Pada ayat tersebut terdapat
suatu kata „uswah, Penulis menerjemahkan Keteladanan dengan tafsiran dari
Hamka pada kitab tafsirnya al-Azhar. Dalam hal tersebut penulis
menggunakan metode tematik agar menemukan pengaruh yang cukup
spesifikasi memahami makna keteladanan. Penulis menemukan pada tafsir al-
Azhar pada surah al-Aḥzāb ayat 4 tersebut menunjukan pada Nabi
Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm tetap teguh dalam pendiriannya
ketika melawan kaum Quraisy dalam perang Badar yg jumlahnya lebih
banyak dibandingkan dengan kaum muslimin yang jauh sedikit. Sedangkan
pada surah al-Mumtahanah menunjukan Nabi Ibrāhīm „alīh al-salām „.
sikapnya yang tetap teguh dalam diri untuk memintakan ampun kepada
ayahnya. Karena ayah musyrik menyembah pada sebuah patung yang dianut
nenek moyang dulu. Sebab Nabi Ibrāhīm „alīh al-salām ingin ayah itu untuk
memeluk agama Islam, namun dengan ajakan dari anaknya tersebut tidak di
perdulikan. Penulis menemukan bahwa keteladanan itu suatu keteguhan
dalam pendirian dalam kebaikan. Seperti halnya seseorang tetap teguh dalam
pendiriannya untuk mencontohkan kepada orang-orang suatu sikap baik
dalam pergaulan.
Kata Kunci: Teks, Konteks, Tafsir buya Hamka, Keteladanan
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk mengawali pengantar ini,
karena Allah yang telah memberikan karunia dan nikmat tak terhingga baik
itu penglihatan, pendengaran, napas, akal untuk berpikir, sehingga penulis
dapat diberikan kesempatan belajar dan menyelesaikan studi strata satu.
Penulis sekali lagi mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas karunia
dan rahmat-Nya yang tidak terbatas dan tidak akan pernah bisa habis
terhitung dengan keterbatasan akal manusia. Ṣalāwah serta salam kita
kirimkan kepada Rasulullah ṣɑllᾱ Allahu ‟alaih wɑ sallɑm, sosok yang
menjadi teladan bagi keluarga, sahabat, tabi„in dan generasi setelahnya yang
menjadi pengikut hingga akhir zaman.
Adapun judul skripsi ini “Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir
Al-Azhar” penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tanpa izin dan nikmat yang telah diberikan Maha Kuasa maka skripsi ini
tidak akan selesai tepat pada waktunya. Penyelesaian skripsi ini juga
melibatkan banyak pihak yang tanpanya karya ini akan banyak mengalami
keterlambatan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan
ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis LC, MA, Rektor
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Dr. Yusuf Rahman, MA, Dekan fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Eva Nugraha. M.Ag , Ketua Program Studi Ilmu al-Qur‟an dan
Tafsir dan bapak Fahrizal Mahdi, MIRKH Sekretaris Program Studi
x
Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir. Yang telah meluangkan waktunya dan
saran teruntuk para mahasiswa untuk keperluan tugas kuliah dalam
mendidik.
4. Dr. M. Suryadinata, M.Ag, Dosen pembimbing skripsi yang selalu
memberikan dedikasinya kepada saya, bersabar memberikan ilmu dan
arahan selama penulis berada di bawah bimbingannya. Beliau juga
telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berarti bagi saya dan
semua mahasiswa lainnya.
5. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu per
satu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya program studi Ilmu al-
Qur‟an dan Tafsir yang ikhlas, tulus dan bersabar untuk mendidik
kami agar menjadi manusia yang berbudi luhur dan berintelektual.
6. KH. Helmi Abdul Mubin, Lc, Pimpinan Pondok Pesantren Ummul
Quro al-Islami Banyusuci Leuwimekar Leuwiliang Bogor. Yang
pernah saya menimba ilmunya di pondok pesantren tersebut, semoga
keberkahan Kyai serta ilmu yang pernah diajarkan kepada santrinya
termasuk saya menjadikan bekal hidup yang baik.
7. Seluruh teman-teman Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir Angkatan 2014,
terutama IQTAF kelas F dan KKN Maura 58 memberi dukungan
kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada pihak-pihak yang turut membantu dan berperan, baik secara
langsung maupun tidak, tanpa mengurangi rasa hormat penulis
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk
membantu pengerjaan skripsi ini. Akhir kata penulis menyadari
bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan
kekeliruan dalam penelitian ini memungkinkan untuk terjadi. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
xiii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................. xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .............................................................................. 8
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ..................................... 8
D. Tujuan penelitian .................................................................................. 9
E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 9
F. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 10
G. Metodologi Penelitian ......................................................................... 14
H. Sistematika Penulisan ......................................................................... 15
BAB II TEORI KETELADANAN SECARA UMUM ................................ 17
A. Pengertian keteladanan ....................................................................... 17
B. Makna Dasar Keteladanan .................................................................. 22
C. Macam-macam Keteladanan ............................................................... 26
BAB III BIOGRAFI ...................................................................................... 37
A. Profil Buya Hamka ............................................................................. 37
1. Riwayat Hidup Hamka .................................................................... 37
2. Intelektual Hamka ........................................................................... 42
3. Pandangan Ulama Terhadap Hamka ............................................... 44
4. Karya-karya Hamka ........................................................................ 47
B. Profil Tafsir al-Azhar .......................................................................... 50
1. Penulisan Kitab Tafsir al- Azhar ..................................................... 51
2. Metode Penulisan Tafsir al-Azhar................................................... 54
C. Corak Tafsir al-Azhar ......................................................................... 56
xiv
1. Sistematika Penafsiran Tafsir al-Azhar ........................................... 58
2. Karakter Khas Tafsir al-Azhar ........................................................ 58
BAB IV ANALISIS KATA KETELADANAN DALAM TAFSIR AL-
AZHAR ........................................................................................................... 63
A. Sikap Teladan Nabi Muhammad ........................................................ 63
1. Sumber Akhlak ................................................................................ 66
B. Sikap Teladan Nabi Ibrāhīm ............................................................... 70
1. Berbuat baik kepada orang tua ........................................................ 72
2. Bertawakal. ...................................................................................... 74
3. Bertaubat ......................................................................................... 75
4. Berdoa ............................................................................................. 77
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 83
A. Kesimpulan ......................................................................................... 83
B. Saran ................................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 85
xv
PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini
berpedoman pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf
Latin dapat dilihat pada halaman berikut:
Huruf arab Nama Huruf latin Nama
ا
alif Tidak
dilambangkan
Tidak
dilambangkan
ba‟ b be ب
ت
ta‟
t
te
ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث
jim j je ج
ح
ḥa
ḥ ha dengan titik di
bawah
kha‟ kh ka dan ha خ
dal d de د
żal ż zet (dengan titik diatas) ذ
ra r er ر
zai z zet ز
sin s es س
ش
syin
sy
es dab ye
xvi
ص
ṣad
ṣ es dengan titik di
bawah
ض
ḍad
ḍ de dengan titik di
bawah
ط
ṭa
ṭ te dengan titik di
bawah
ظ
ẓa
ẓ zet dengan titik di
bawah
ain „_ apostrof terbalik„ ع
ghain g ge غ
ؼ
fa
f
fa
qaf q qi ؽ
ؾ
kaf
k
ka
lam l el ؿ
ـ
mim
m
em
nun n en ف
wau w we ك
ha h ha ق
hamzah _ʼ apostrof ء
ya‟ y ye م
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (ʼ).
B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xvii
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Vokal Nama Latin Keterangan
ا
Fatḥah
a
a
ا
Kasrah
i
i
ا
Ḍammah
u
u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,
yaitu:
Tanda Nama Latin Keterangan
ىىيFatḥaḥ dan ya ai a dan i
ىىوFatḥaḥ dan Wau au a dan u
Contoh:
ḥaula : ىوؿ Kaifa : كيف
C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan
huruf
Nama
Latin
Keterangan
ب
Fatḥaḥ dan alif
ā a dengan garis di
atas
Kasrah dan Ya‟ ī i dengan garis di atas ب
ييو
Ḍammah dan Waw
ū u dengan garis di
atas
Contoh:
xviii
māta : مىات
ramā : رمىى
qīla : قيلى
yamūtu : يىيوتي
A. Ta marbūṭah
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥaḥ. kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
rauḍah al-aṭfāl : رىكضىةياألىطفاؿ
ىديػنىةيالفىاضلىةي al-madīnah al-fāḍilah : امل
al-ḥikmah : احلكمىةي
B. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
rabbanā : رىبػنىا
نىا najjaīnā : نىيػ
al-ḥaqq : احلىق
al-ḥajj : احلىج
xix
nu“ima : نػيعمى
aduwwun„: عىديك
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir kata dan didahului oleh huruf kasrah
ى ) ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).
Contoh:
Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: عىلي
.Arabī (bukan „Arabi atau „Araby)„ : عىرىب
C. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟rifah) ال
ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
al-syams (bukan asy-syamsu) : الشىمسي
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزىلزىلىةي
al-falsafah : الفىلسىفىةي
دي al-bilādu : البلى
D. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif. Contohnya:
ميريكفى ta‟murū : تى
‟al-nau : النػىوءي
xx
syai‟un : شىيءه
umirtu : أيمرتي
E. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), sunnah, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-shabab
F. Lafẓ al-Jalālah (هللا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), Transliterasi
tanpa huruf hamzah. Contoh:
billāh بالل dīnullāh دينالل
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ-
jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:
hum fī raḥmatillāh هم في رحمةللا
xxi
G. Huruf Kapital
Walaupun system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasikan huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri diketahui oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa māMuḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi bi Bakkata mubārakan
Syahrul Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‟ān
Naṣir al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Ghazālī
Al-Munqiż minhal-Ḍalāl
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan perlu adanya keteladanan antara sesama manusia
agar yang lakukan menjadikan suatu ibadah. Pada bukunya Buya Hamka
berisikan suatu kalimat yang perlu adanya suatu panutan/teladan yang
baik, seperti halnya mencontohkan suatu keteladanan yang baik itu
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm, mewariskan dua
pusaka/pembimbing hidup yaitu al-Qur‟an dan hadis yang berisikan suatu
hal agar selamat dunia dan akhirat.
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm adalah suri teladan yang
patut dicontoh bagi seorang muslim yang baik. Rasul mengatakan bahwa
pusat eksistensi manusia yang menentukan kualitas kepribadiannya adalah
qalb. Manusia memiliki potensi qalb untuk merenung, menyadari,
menghayati, memilih mana yang baik dan buruk. Kata qolb yang telah
diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi “kalbu” ini mengandung
pengertian sumber kesadaran batiniah atau dapat dimaksud dengan hati
nurani.1
Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm sukses dalam
mensiarkan agama Islam dalam media dakwahnya, yang mana rasululah
selalu mengedepankan keteladanan pada setiap orang-orang yang
mengenal Islam..2
Keteladanan Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm bukan
keteladanan yang absurd (tidak masuk akal) dan mustahil dicontoh oleh
manusia umumnya. Ketika Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
1 Hamadani Bakran Adz-dzakiey, Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelligence,
(Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2006), 5. 2 Untung M.S, Muhammad Sang Pendidik, (Semarang:Pustaka Rizki, 2005), 160.
2
sallɑm berinteraksi dengan Allah subḥāna wa ta‟ala Maha pencipta ketika
di sepertiga malamnya untuk beribadah dan berdoa. Rasul ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm juga berinteraksi kepada setiap orang-orang serta
lingkungan, semuanya tindakan yang dilakukan dari perkataannya
perbuatan yang dilakukan mengandung sebuah unsur keteladanan yang
dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi moral bagi seseorang untuk
melakukan hal yang sama. Interaksi edukatif (mendidik) yang dilakukan
oleh Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm . Hal tersebut dapat
dirumuskan dengan: Akhlak manusia terhadap Allah subḥāna wa ta‟ala
dalam suatu ibadah, akhlak manusia dengan dirinya sendiri dalam
memecahkan suatu yang baik, akhlak manusia dengan manusia lainnya
seperti hal saling tolong menolong, dan ahklak manusia dengan
lingkungan seperti hal agar selalu menjaga lingkungan baik itu menjaga
alam sekitar serta merawatnya agar tidak dirusak.3
Dalam kamus besar Bahasa indonesia disebutkan bahwa keteladanan
dasar kata teladan yaitu: “(perbuatan atau barang) yang patut ditiru dan
dicontoh”4 Oleh karena itu keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru
dan dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan dengan kata
„uswah dan bentuk dari huruf-huruf; hamzah, Syin, dan Waw. Artinya
pengobatan dan perbaikan5
Dengan demikian kata keteladanan atau „uswah ḥasanah adalah hal-
hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain yang memiliki
nilai positif. Sehingga yang dikehendaki dengan keteladanan („uswah) di
sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan
3 Untung M.S, Muhammad Sang Pendidik, cet. I (Semarang:Pustaka Rizki, 2005),
, 163. 4 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), 22. 5 al-Syaik al-Imam Muhammad bin Abi Bakr Ibn Abdul Qadir Al-Razi, Mukhtar
al-Shihah (Lebanon: Maktabah, 1980), 7.
3
Islam, yaitu keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian uswatun
hasanah.
Keteladanaan dalam term „uswah dalam al-Qur‟an surah al-Aḥzāb
ayat 21.
ى كىاليػىوـى الهخرى ى لىقىد كىافى لىكيم ف رىسيوؿ الله ايسوىةه حىسىنىةه لمىن كىافى يػىرجيوا الله كىذىكىرى اللهثيػرنا كى
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia
banyak menyebut Allah." (Qs. al- Aḥzāb/ 33: 21)
Konteks ayat di atas menunjukkan posisi Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm sama seperti dalam wacana, perbuatan, dan pengobatan,
juga pembiaran tersebut merupakan permohonan dari Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā terhadap manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm. di bagian surah al-Aḥzāb: 21 mengungkapkan untuk
melambangkan toleransi, sekalipun isu-isu yang diberikan oleh Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā. Ada juga pendahuluan yang diberikan Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā kepada Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
akan memberikan bantuan dan kemenangan sebagaimana dijanjikan
kepadanya.6
Jelas Muḥammad jamāluddīn al-Qāsimī mengatakan dalam tafsirnya
bahwasanya Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm itu dalam dirinya
terdapat suri teladan baik contohnya agar orang yang dapat mengharap
rahmat Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan di hari kiamat banyak yang
6 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Taisir al-aliyyul Qadir li intisari tafsir ibnu katsir,
Terj. Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,jilid 3, (Jakarta
G situasi gema insani press,1989), 841.
4
memanggil Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Tentu halnya suatu Akhlak dan
perilaku pada Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm terdapat suri
teladan yang baik dikarena ketetapan dan ketegaran hati disaat
menghadapi cobaan dan situasi yang berat. Ini sangat atau diperlukan serta
didapati kesabaran ketika menghadapi cobaan dan ancaman. Jiwa beliau
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm tetap tabah dan tenang dalam
menghadapi segala situasi personal yang dihadapinya. Tidak putus asa
dalam menghadapi kesulitan dan tidak merasa rendah terhadap hal-hal
yang besar. Walaupun dalam keadaan lemah beliau Rasulullah ṣɑllā
Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm tetap teguh dan sabar sebagaimana orang yang
beriman untuk selalu unggul. Dan sesungguhnya siapa yang bisa bersabar
dalam berdo‟a kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dalam menghadapi
situasi persoalan yang rumit maka orang tersebut punya derajat tinggi.7
Menurut Abū Ja‟far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī menegaskan
pada tafsirannya bahwa adanya perbedaan para Qurra‟ (orang yang pandai
suatu membaca al-Qur‟an) dalam membaca firman („uswah) umumnya
para qurra‟ Mesir selain Imam „Ashim bin Abi Nujud, mengucapkan
(„uswah) dengan kasrah Alif. Walaupun Imam „Ashim Membaca („uswah)
dengan ḍammah Alif. Ayat ini diturunkan merupakan cobaan dari Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm dan para sahabat-sahabatnya
(orang mukmin) di Madinah. Maka barangsiapa yang mengharapkan
pahala dari Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan rahmatnya nanti di hari akhirat
maka dia tidak akan merasa cukup/senang dengan dirinya sendiri. Tetapi
dengan itu dia merasa mempunyai contoh teladan untuk selalu diikuti di
7 Muḥammad jamāluddīn al-Qāsimī, Tafsir al-Qasimi al Musamma Mahasin al
ta‟wil, juz 13, (Beirut: Darul al Fikr, 1924), 129.
5
manapun dia berada.8 Senada dengan hal tersebut, Imam Sulaiman Ibn
Umar menafsirkan bahwa kalian telah mempunyai contoh teladan dalam
diri Nabi, yang mana beliau adalah mencurahkan tenaganya untuk
menolong agama Allah dengan cara ikut bertempur dalam perang
Khandak. Juga dia saat beliau terluka wajah dan gigi depannya, serta
terbunuhnya paman beliau Hamzah dan bagaimana beliau juga merasakan
lapar, meski demikian beliau tetap sabar, berharap pertolongan kepada
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan selalu ikhlas dengan apa pun yang terjadi
itu segalanya.9
Pada dasarnya ayat tersebut menunjukan pada pribadi Nabi
Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm. Dengan demikian, sikap
kepribadian/keteladanan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
hendaknya harus dimiliki oleh seorang pendidik, ini berarti seorang guru
atau orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk jiwa anak.
Sifat sabar, teguh pendirian akhlakul karimah merupakan sifat yang harus
ditanamkan kepada mereka. Sehingga mereka akan memiliki jiwa dan
mental yang kuat dengan kepribadian yang baik serta tidak memiliki sifat
pengecut.
Ayat tersebut diulang pada Qs. al-Mumtaḥanah/ 60: 4 dan 6:
ابػرهىيمى كىالذينى مىعىو ف قىد كىانىت لىكيم ايسوىةه حىسىنىةه ؤيا اذ قىاليوا لقىومهم ان بػيرىءه
ا منكيم كىما تػىعبيديكفى من ديكف الله ءي اىبىدناكىةي كىالبػىغضىا نىكيمي العىدى نػىنىا كىبػىيػ ا بػىيػ كىفىرنى بكيم كىبىدى
دىهحىته تػيؤمنػيوا بلله كىح ىستػىغفرىف لىكى كىمىا اىملكي لىكى منى ال قػىوؿى ابػرهىيمى لىبيو لىري الله من شىيءو نىا كىالىيكى المىصيػ لنىا كىالىيكى اىنػىبػ رىبػنىا عىلىيكى تػىوىك
8 Abi Ja‟far Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabari, jami al-Bayan „An Ta‟wili ayī al-
Qur‟an, Juz 19, (Beirut: Darul al-Fikr, 1924), 143. 9 Imam Sulaiman Ibn Umar Al-Ajyay al-Syafi‟y Al-Syahir bil Jamal, Al
Futuuhhaat al Ilhiyyah Bi Taudiihi Tafsir Al-jalalain Lidawaaqk al-Khafiyah, juz 7
(Beirut:Dar Al Kutub al-Ilmiyah, 1204 H), 162.
6
“Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrāhīm „alīh
al-salām dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka
berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu
dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari
(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan
dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada
Allah saja,” kecuali perkataan Ibrāhīm „alīh al-salām kepada ayahnya,
”Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama
sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” (Ibrāhīm „alīh
al-salām berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami
bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada
Engkaulah kami kembali,” (Qs. al-Mumtaḥanah/ 60: 4).
ى كىاليػىوـى الهخرى لىقىد كىافى لىكيم فيهم ايسوىةه حىسىنىةه لمىن كىافى يػىرجيوا ى الله كىمىن يػتػىوىؿ فىاف الله ىيوى الغىن احلىميدي
“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrāhīm „alīh al-salām dan umatnya)
ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang
mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan
barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang
Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. al-Mumtaḥanah/ 60:6)
Ibnu Katsir mengatakan dalam al-Qur'an, Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā berfirman kepada umat untuk tidak antagonis terhadap orang-orang
untuk memisahkan diri dari mereka, Pasti ada teladan yang tulus untuk
pada Ibrāhīm „alīh al-salām dan orang-orang yang bersamanya, (Dan
orang-orang yang beriman kepadanya) dari mengikuti kepada Nabi.
Karena memohon pengampunan kepada Tuhan terhadap ayahnya
meskipun faktanya itu adalah musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā.10
Jelas Buya Hamka pada Tafsir al-Azhar secara eksplisit bahwa Nabi
Ibrāhīm „Alaīh al-salām meminta pengampunan ayahnya kepada Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā, akan tetapi ayahnya tidak menghiraukan apa yang
10 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, Kemudahan Dari Allah ringkasan Tafsir Ibn
Katsir, Jilid 3. terj., Syihabuddin, (Jakarta : Gema Insani Press,1989), 671.
7
diperbuat Nabi Ibrāhīm „alīh al-salām. Karena ayah tetap tidak merespon
yang dilakukan Nabi Ibrāhīm „Alaīh al-salam untuk menyembah Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā akan tetapi kembali menyembah patung yg diajar
nenek moyang mereka. Nabi Ibrāhīm „Alaīh al-salam tidak pantang
menyerah dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā.
Dia mengatakan kepada ayahnya dia akan benar-benar meminta
pengampunan karena kapasitasnya untuk memohon kepada Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā kekuatannya dekat dengan itu. Namun, setelah itu
jaminan tidak puas oleh ayahnya atas meninggalnya agama lamanya.
Pokoknya tidak mengganggu sentimen dan benar-benar berarti Nabi
Ibrāhīm „Alaīh al-salam terhadap ayahnya, sepanjang garis-garis ini dia
tahu itu tentang ayahnya sebenarnya adalah musuh Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā.11
Penjelasan tentang keteladanan amat perlu sekali untuk dikaji lebih
dalam, mengingat kasus-kasus perilaku yang kurang baik di masyarakat di
zaman sekarang yang patut diperbaiki dari segi akhlak, moral, sopan
santun, budi pekerti terutama pendidikan keteladanan. Berdasarkan
penjelasan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian
dengan Metode Tafsir Tematik dalam kajian ini, guna menghadirkan
gambaran yang sistematis dan pemahaman yang utuh mengenai tema
keteladanan. Penelitian ini diberi judul: Keteladanan perspektif Hamka
dalam kajian Kitab Al-Azhar. Saya mengambil karya Hamka dengan
Tafsir al-Azhar sebagai rujukan, karena penulis merasa ingin mengkajinya
lagi agar dapat dipahami dengan baik, dengan mufasir tersebut karena
sangat bagus untuk dijadikan sebuah penelitian skripsi penulis.
11
Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, jilid 9 cet. IV (Singapura
Pustaka Nasional PTE ELTD,1999), 7296.
8
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, permasalahan
yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:
a. Jelaskan penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsirnya
mengenai keteladanan ?
b. Apa maksud keteladanan menurut Buya Hamka dalam tafsir al
azhar pada Qs. al- Aḥzāb/ 33: 21 dan Qs. al-Mumtaḥanah/ 60: 4
dan 6 tersebut ?
c. Jelaskan istilah keteladanan dalam al-Qur‟an?
d. Bagaimana Buya Hamka dalam memahami cara pandang
keteladanan?
e. Apa yang membedakan dengan penafsir lain mengenai maksud
keteladanan tersebut ?
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
1 Agar dalam penelitian ini tersusun dengan baik dan lebih
mendalam maka penulis membatasi masalah dengan melakukan
pencarian kata „uswah dalam kitab al-Mu‟jam al-Mufahras li al-
Fᾱż al-Qur‟an al-Karῑm karya Muhammad Fu‟ᾱd „Abd al-Bᾱqῑ
dan menemukan 3 ayat yakni: Qs. al- Aḥzāb/ 33: 21, Qs. al-
Mumtaḥanah/ 60: 4 dan 6.
2 Dari beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti dapat
merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini,
yaitu : bagaimana Buya Hamka memahami kata „uswah dalam
kitab tafsir al-Azhar Qs. al-Aḥzāb/ 33: 21 dan al-Mumtaḥanah ayat
4 dan 6.
9
D. Tujuan penelitian
Mengingat definisi masalah, asumsi yang harus dicapai dalam
penyelidikan ini, misalnya:
1. Untuk mengetahui jauh dalam memahami arti ayat-ayat
keteladanan dari seorang mufassir buya Hamka.
2. Untuk bisa mencontohkan keteladanan yang baik bagi generasi
muda khusus bagi para remaja dalam suatu lingkungan
pergaulan.
3. Untuk mencontohkan isi Tafsir Qs. al-Aḥzāb/ 33: 21, suatu
sikap Nabi Muhammad saw yang teguh dalam pendiriannya.
4. Merubah perilaku dalam pergaulan bebas terhadap suatu
lingkungan masyarakat yang suka meresahkan.
5. Untuk memenuhi prasyarat tugas dan keinginan terakhir
memperoleh pendidikan perguruan tinggi empat tahun Strata 1
(S1) dari lapangan UIN Syarif Hidayatullah dari tenaga kerja
Program Studi Ushuluddin al-Qur'an dan Tafsir
E. Manfaat Penelitian
Menambahkan kontribusi dalam hal kajian dan memahami suatu
perkembangan pada al-Qur‟an, khususnya pada ayat-ayat yang
menyinggung masalah keteladanan dalam al-Qur‟an, serta menambah
Khazanah kepustakaan dan intelektual Islam terutama dalam studi
penafsiran al-Qur‟an. Di samping itu, penelitian ini juga dapat berguna
sebagai bahan rujukan bagi siapa saja yang ingin meneliti atau
mengembangkan penelitiannya secara sempurna.
Manfaat skripsi ini untuk Program Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir.
peneliti akan melengkapi makna dan arti keteladanan. yang perlu
10
dipelajari oleh beberapa orang penelitian sebelumnya, dan menambahkan
apa yang belum dipelajari sebelumnya juga.
Adapun kegunaan dari penelitian ini secara non akademik adalah:
1. Agar para pembaca bisa memahami suatu gambaran dan
pemahaman tentang keteladanan.
2. Agar Keteladanan yang dikaji mampu diaplikasikan ke setiap
orang terutama bagi penulis sendiri.
3. Untuk menambah Khazanah keilmuan serta dapat memahami
kandungan ayat al-Qur‟an.
F. Tinjauan Pustaka
Skripsi, Siti Barokatul Amamiyah tentang “Metode Keteladanan
(„uswah ḥasanah) Dalam Pendidikan Islam Perspektif al-Qur‟an” skripsi
ini menjelaskan pendidikan keteladanan prinsip dalam meluruskan
penyimpangan moral dan perilaku anak-anak dalam meningkatkan
kualitas menuju kemuliaan berakhlak. Sepanjang garis-garis ini, sebagai
guru yang sah dan dipercaya oleh wali, dengan berakhlak yang terhormat
kemungkinan bahwa anak muda akan tumbuh dengan karakteristik besar
sepanjang kehidupan sehari-hari. Pada saat itu jika anak muda dibesarkan
dengan teguran dan agresi, dia akan mencari tahu bagaimana untuk
menghidupkan kembali dan pertempuran, melainkan anak yang dibesarkan
dengan simpati dan dedikasi besar dia akan belajar kesetaraan dan
menemukan cinta dalam hidupnya.12
12
Siti Barokatul Amamiya “metode keteladanan (uswah hasanah) dalam
pendidikan islam perspektif al-qur‟an” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya 2015). 20.
11
Karya buku Yunan Yusuf dalam bukunya membahas tentang “corak
pemikiran kalam Hamka dalam Tafsir al-Azhar”. percakapan ini dalam
sejarah hidup Hamka dengan siklus kreatif yang sangat luar biasa dan luar
biasa pada Pemahaman al-Azhar oleh Hamka, , penulis menjelaskan yang
sangat komprehensif dan cermat, penulisan menguraikan dengan cermat
dan nyata akan pemikiran Hamka dalam tafsirnya.13
Artikel, Fachry Ali tentang “Hamka dan Masyarakat Islam
Indonesia‟ catatan pendahuluan Riwayat dan Perjuangannya” artikel ini
menyimpulkan bahwa Hamka seorang pembaharu Islam di indonesia,
dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya, Hamka memiliki
kredibilitas yang tinggi. Pemahamanya yang luas mengenai agama dan
juga pemikiran-pemikiran membuat Hamka menjadi seorang yang
berpandangan luas. Hamka adalah seorang ulama yang posisi terdepan
dalam masyarakat Islam modern Indonesia yang sedang mengalami proses
modernisasi.14
Skripsi, Abdur Rahim tentang “Konsep Akhlak Menurut Hamka
(1908-1981)” skripsi ini menjelaskan Kualitas mendalam memiliki
pekerjaan besar dalam sistem biologis manusia, setiap perkembangan
orang tidak dapat diisolasi dari akhlak yang mengenali orang dari berbagai
makhluk.15
13
Yunan Yusuf, M, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: sebuah Telaah
Tentang Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam, cet 1 (Jakarta: Pustaka Panjim as, 1990)
35 14
Fachry Ali, “Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia: Catatan Pendauluan Riwayat dan peruangannya”. Dalam Majalah Prisma, Februari, 1983, 23 . 15
Abd Rahim, “Konsep Akhlak Menurut Hamka (1908-1981)” ( Skripsi S1.,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013). 24.
12
Skripsi, Siti lestari tentang “Pemikiran Hamka tentang pendidik
dalam pendidikan Islam” jurnal ini menjelaskan tentang pemikiran yang
berati proses, perbuatan, cara memikir problem yang memerlukan
pemecahan, Hamka merupakan salah satu pemikir pendidikan yang
banyak memberikan tawaran-tawaran konsep pendidikan Islam yang benar
yaitu yang sejalan dengan al-Qur‟an dan hadis, pendidik dalam Islam
adalah orang-orang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta
didik, baik potensi afektif, kognitif (cipta) atau Psikomotorik (karsa).16
Jurnal, Shabahus Surur tentang “Pembaruan Pendidikan Islam
Perspektif Hamka” jurnal ini menjelaskan bahwa pembaruan sebuah
keharusan. Para Ulama sepakat bahwa pembaruan (tajdid) harus dilakukan
agar pokok-pokok ajaran Islam diterima dan dilaksanakan oleh
masyarakat.17
Skripsi, Ahmad Muslim tentang “Corak Penafsiran Tasawuf Hamka
(Studi Penafsiran ayat-ayat Tasawuf dalam Tafsir al-Azhar)” Skripsi ini
tertuju pada Tasawuf Hamka adalah tasawuf yang dirancang Tafsir Isyari,
yaitu tasawuf tergantung pada prinsip-prinsip logis yang tulus dan masuk
akal. sama seperti terjemahan pembiaran al-Qur'an dan pemahaman isyari
adalah al-Qur'an menggabungkan apa itu zahir dan mental. Pentingnya
zahir adalah isi pembicaran al-Qur'an sementara pentingnya jiwa adalah
pentingnya tanda menyerupai pemeriksaan magis berdasarkan ruhiyyah
riyadhah, atau kegiatan mendalam dengan arah melalui suara batin atau
16
Siti Lestari, “Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan dalam Pendidikan Islam”
(Skripsi S1., Intituts Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010). 18. 17
Shabah Surur, “pembaruan Pendidikan Islam Perspektif Hamka” . Jurnal,
Universitas Darussalam Gontor. Vol. 2, no. 1 (Januari 2009). 25.
13
disebut mukasyafah, pertinensi tasawuf Hamka dengan kehidupan saat ini
memiliki selaras.18
Jurnal, Usep Taufik Hidayat tentang “Tafsir al-Azhar: Menyelami
Kedalaman Tasawuf Hamka” Jurnal ini tidak berkarakter dan istilah
tasawuf sepenuhnya namun Hamka hanya mencirikan istilah-istilah yang
membutuhkan pengaturan sosial apa adanya. Seperti gagasan tentang
tasawuf secara komprehensif dalam sudut pandangnya sendiri, hipotesis
Tasawuf tradisional dilengkapi dengan pengaturan sosio kultural
masyarakat Jawa dan Melayu saat ini.19
Karya Ilmiah, M. Sirajuddin tentang “Konsep Ulama menurut
Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” karya ilmiah ini menjelaskan tentang
ulama itu bukan hanya ahli di bidang pengetahuan agama saja tetapi juga
seorang yang ahli mengkaji masalah ilmu agama juga dengan bertujuan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā .
Imam Faizal dalam skripsinya menjelaskan tentang “Pemikiran
Hamka tentang guru” skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Hamka guru
adalah sosok yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan
mengantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas,
Hamka lebih menekankan aspek pendidikan jasmani dan rohani.20
18
Ahmad Muslim, “Corak Penafsiran Tasawuf Hamka (Studi Penafsiran Tasawuf
Dalam Tafsir Al-Azhar” (Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2016). 19
Usep Taufik Hidayat, “Tafsir al-Azhar : Menyelami Kedalam Tasawuf Hamka”
Jurnal Fakultas Adab Humaniora, vol. 1, no. 2 (Oktober 2015): 213-215. 20
Imam Faizal, “Pemikiran Hamka tentang Guru” (Skripsi S1., Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016), 15.
14
G. Metodologi Penelitian
Dalam penulisan sebuah karya ilmiah harus menggunakan
metodologi penelitian. Metode adalah cara yang digunakan untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata
agar tujuan telah disusun tercapai secara optimal.21
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, jenis penulis ini
library research yaitu teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-
literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada sehingga
diperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan
masalah yang dipecahkan.22
Adapun teknik penulisan skripsi ini
merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Artikel,
dan Disertasi” yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Sumber data
Dalam penyelidikan, jelas, pencipta menggunakan dua sumber
informasi, yang terdiri dari sumber informasi penting dan sumber
informasi tambahan.
a. Sumber informasi mendasar data primer23
dalam menulis
sebuah skripsi ini perlu merujuk kepada sebuah kitab suci al-
21
Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan
(Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008), 147. 22
Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003),
27. 23
“Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak
pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab riset atau
penelitian,” Diakses 25 November 2017. http://accounting-
media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1
15
Qur‟an dan hadits yang berkaitan dengan ayat-ayat
keteladanan. Adapun literatur pokok yang menjadi acuan
dalam penelitian ini merujuk pada kitab tafsir al-Azhar karya
Hamka
b. Pokok sumber data sekunder24
dalam sebuah penelitian ini
penulis perlu merujuk pada kitab al-Mu‟jam al-Mufahras li al-
Fᾱż al-Qur‟an al-Karῑm pada karya Muḥammad Fu‟ᾱd „Abd al-
Bᾱqῑ kamus-kamus bahasa Arab, ensiklopedi, dan merujuk pada
buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan makalah yang
berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
3. Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data-data dari
sumber primer dan sekunder, penulis perlu mencoba mengolah data
tersebut dengan menggunakan metode tematik25
. Penulis menggunakan
metode tematik karena penulis mengumpulkan ayat-ayat terlebih dahulu,
kemudian penulis menganalisisnya.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan merupakan hal yang penting karena
mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-
masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksud agar
tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan dan tidak keluar dari
pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:
24
Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab riset atau
penelitian,” Diakses 25 November 2017, http://accounting-
media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1 25
„Abd al-Hayy al-Farmᾱwi, Al-Bidᾱyah fi al-Tafsir al-Mauḏū‟i: Dirasah
Manhajiyyah Mau ḏiyyah (Cairo: Al-Hadharah al-„Arabiyyah, 1977), 23.
16
Bab I berisikan pendahuluan. Bab ini dimulai dari latar belakang
masalah, Identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan
manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metodologi penelitian
dan sistematika penulisan.
Bab II, berisi tentang gambaran umum konsep keteladanan yang
meliputi berupa pengertian keteladanan, macam-macam keteladanan,
tujuan dan manfaat keteladanan.
Bab III, berisi tentang biografi Hamka lalu seputar kehidupan buya
Hamka dan karya-karyanya seperti karya kitab tafsirnya al-Azhar, historis
kitab tafsir al-Azhar, sumber dan metode penafsiran kitab tafsir al-Azhar,
corak dan sistematika penafsiran kitab tafsir al-Azhar
Bab IV, berisi tentang Analisis makna kata khusus keteladanan
dalam kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka pada surah al-Aḥzāb
ayat:21 dan surah al-Mumtahanah ayat 4 dan 6.
Bab V, hasil akhir atau penutup dari penelitian skripsi ini, yang
merupakan kesimpulan yaitu jawaban dari pertanyaan yang diajukan
dalam rumusan masalah serta berikan saran-saran mengenai penelitian
yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan dan kekurangan pada
penelitian yang terkait.
17
BAB II
TEORI KETELADANAN SECARA UMUM
A. Pengertian keteladanan
Dalam hal pandangan linguistik, "keteladanan" dasar kata adalah
"teladan" dalam arti itu contoh, sesuatu yang patut ditiru karena itu baik,
seperti halnya dengan perilaku, perbuatan dan kata-kata. Kemudian kata
"contoh" diberikan dengan awalan "ke" dan akhiran "an", sehingga
menjadi kata "ketegasan" yang berarti sesuatu yang memberi contoh atau
contoh yang patut ditiru dalam kebaikan. Tetapi dalam bahasa Arab
contohnya berasal dari kata qudwah. Menurut Yahyā Jalāludin, qudwah
berarti „uswah, yaitu ikutan, mengikuti seperti yang diikuti.1
Seperti halnya di dalam al-Qur‟an kata teladan diibaratkan dengan
kata-kata „uswah yang kemudian dilekatkan dengan kata hasanah,
sehingga menjadi padangan kata ‟uswah ḥasanah yang berarti teladan
yang baik.
Dalam al-Qur'an kata uswah dalam beberapa ayat al-Qur'an melekat
pada sikap dan tindakan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm (Nabi
Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm) juga sering melekat pada Nabi
Ibrāhīm Alaīhi al-salām untuk menegaskan keakuratan Rasulullah ṣɑllā
Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm pada, kemudian menjelaskan tindakan yang yang
memiliki nilai positif Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm yang
terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an. Ada juga keberadaan
yamg yang dimaksud oleh Heri Jauhari Muchtar, keteladanan adalah suatu
1 A. Zainal Abidin, Memperkembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam
di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 96
18
bentuk pengajaran dalam sebuah memberikan contoh yang baik kepada
peserta didiknya tersebut, Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.2
‟Abdūllah Nāṣiḥ ‟Ulwᾱn keteladan adalah jenis instruksi yang kuat
untuk anak-anak dalam menumbuhkan penemuan seorang guru. Abdullah
‟Abdūllah Nāṣiḥ ‟Ulwᾱn juga membangun penilaiannya dengan pertikaian
dari Charles Schaefer, kehadiran sinyal non verbal yang signifikan dan
memberikan ilustrasi peniruan yang masuk akal. Menurut Nur Uhbiyati
dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam menuliskan bahwa metode yang
cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak adalah metode pemberian
contoh dan teladan.3
Sepanjang garis-garis ini alasan prinsip-prinsip adalah untuk
mengajar anak-anak dengan menetapkan model asli („uswah ḥasanah)
untuk menjadi contoh yang baik yang layak dalam kata-kata, mentalitas
dan hal-hal yang mengandung besar. sejak di sekolah Islam yang
diinstruksikan kepada anak muda untuk berdampak besar yang dia
edukasi.
Dalam hal ketegasan, itu akan menimbulkan kepribadian sensitif
untuk melakukan ketaatan. karena anak melihat sudut pandang orang-
orang di sekitarnya seseorang yang dikagumi dan diidolakan. Karena tidak
akan terpengaruh oleh karakter fiksi yang disajikan oleh media televisi,
karena ayah dan ibu adalah panutan yang baik agar dapat menjadikan anak
yang saleh dan sholehah.
Selain itu, keteladan akan memunculkan kepribadian yang peka
dalam menjalankan ketaatan. Hal ini disebabkan anak melihat orang-orang
2 Heri jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, cet. I, (Bandung: PT. Rosdakarya,
2005), 224. 3 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 117.
19
yang sekitarnya adalah pribadi yang dikagumi dan diidolakan. Anak tidak
akan terpengaruh dengan tokoh fiktif yang dihadirkan oleh media televisi,
karena ayah dan ibunya lah menjadi panutan anak dalam kesalehan.
Dengan demikian proses pendidikan akan berjalan dengan penuh makna
jika kedisiplinan dalam ibadah misalnya, akan terlihat dari orang tuanya
yang bersegera shalat saat mendengar adzan. Ayahnya segera bergegas
pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama‟ah. Ibu segera
menghentikan segala aktivitas untuk menunaikan kewajiban dengan penuh
kerelaan. Hal ini akan menjadikan anak begitu antusias meniru kebiasaan
tersebut, terlebih jika pendidikan keteladanan ini diberlakukan sejak anak
usia dini. Sebab anak akan memiliki kemampuan untuk menyerap
pemahaman lebih kuat dan membekas. Sehingga orang tua diharapkan
untuk selalu memberikan apresiasi positif kepada anak, baik melalui
pujian maupun melalui teladan yang baik.
Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling
menyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk
akhlak pada diri anak. Hal ini dikarenakan pendidikan keteladanan
merupakan metode mudah dalam pandangan anak, yang akan ditiru dalam
tindakannya, bahkan akan terpatri dalam jiwa dan perasaannya dan
tercermin dalam ucapan dan perbuatannya.4
Sekolah Islam memiliki teknik rata-rata dalam menerapkan ide ideal
yang diinstruksikan dalam interaksi instruktif. Pelajaran tersebut didapat
dari ungkapan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan hadis. Dalam hal sekolah
yang harus dilakukan untuk memahami akuisisi, dalam satu muslim
persyaratan untuk mengamati standar Islam dengan baik. Karena dengan
akurasi ini anak akan mendapatkan dari perbuatan yang layak baginya.
4 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, cet. V (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 174.
20
Agar supaya anak akan cenderung mengingat sesuatu yang dapat
mempengaruhi jiwanya. Seseorang pun akan mudahnya melupakan
sesuatu yang didengarkannya dan dilihatnya. Akan tetapi tidak dengan
sesuatu yang berkesan di dalam hatinya. Sebab keteladanan adalah metode
utama dalam sebuah pendidikan. Terutama sebagai ayah dan ibunya yang
menginginkan anak-anaknya terbaik, maka dari itu perlu menjadikan
contohkan yang terbaik terlebih dahulu.5
Dalam sebuah pendidikan Islam, metode keteladanan perlu lebih
banyak diberikan dalam suatu bentuk tindakan. dikarenakan, keimanan
pada seseorang adalah suatu keberhasilan, agar dapat melakukan dengan
sebuah praktek (pengamalan) baik dalam suatu kegiatan ubudiyah maupun
dalam muamalah diantara manusia.6 Adapun buah dari sebuah ilmu yang
didapat adalah sebuah kesalahan. Begitu juga dengan anak-anak dapat
memiliki sebuah konsep mengenai dunia bagaimana hidup dan bertumbuh
tersebut dari ide-ide yang diasosiasikan nya pada suatu objek tertentu dan
dengan kegiatan-kegiatan yang positif terdapat di sekitarnya.7 Oleh sebab
itu anak-anak cenderung dengan menjadikan keadaan sekitar menjadi
bahan belajar. Tentunya dalam hal aktivitas yang dialami, seperti
perkataan yang didengar, dan tindakan yang mereka terima dari berbagai
orang yang ada di sekitarnya akan tercermin dalam sikap kepribadiannya.
Dalam sebuah mendidik perlunya untuk memberikan contoh sebab
dengan halnya itulah cara yang paling banyak meninggalkan kesan.8
5 Saiful falah, Parents Power “Membangun karakter Anak melalui Pendidikan
Keluarga (Jakarta: epublika, 2014), 246. 6 Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, cet. II (Bandung:CV
Pustaka Setia, 2001), 182. 7 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, cet ke-5 ( Jakarta:
bumi Aksara, 2011), , 44. 8 Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik, cet. 1 (Jakarta: Al-Huda, 2006) ,
307.
21
keteladanan hal menjadi magnet untuk menarik perhatian yang diikuti oleh
anak disebabkan dengan melihat figur yang menjadi suatu sumber utama
agar mengajarkan kebaikan.
Dengan Keteladanan tersebut adalah suatu metode utama di samping
cara yang lainnya dalam sebuah pendidikan Islam, suatu yang dapat
dijadikan untuk media pendidikan, dengan memperoleh secara efektif agar
dapat membentuk suatu kepribadian anak didiknya menjadi suatu yang
berakhlak mulia. Karena Keteladanan itu dapat disebut dengan suri
teladan. Pada ayat al-Qur‟an terdapat sebuah kata dengan uswah yang
mana makna sifat itu di belakangnya, seperti hasanah yang berarti baik,
sehingga mengandung kata ungkapan „uswah ḥasanah yang berarti suri
teladan yang baik.9
Dalam sebuah Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang dapat
dipahami serta dikembangkan dari beberapa pengajaran dan nilai-nilai
fundamental yang mana terkandung pada sumber dasarnya yaitu al-Qur‟an
dan al-Sunnah. Karena itu pendidikan Islam berupa pemikiran dan teori
pendidikan yang dibangun dari sumber-sumber tersebut.10
Adapun dengan
ada dua sumber tersebut yakni al-Qur‟an dan al-Sunnah, mereka juga
mengikuti kesepakatan musyawarah para ulama, serta warisan sejarah
Islam.11
Keteladanan merupakan sebuah pendidikan metode yang sangat
berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dalam
9 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
95. 10
Al-Maghribi Ibn al-Said al-Maghribi, Beginilah seharusnya Mendidik Anak, cet.
V (Jakarta: Darul Haq, 2007), 131.
11
Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
95.
22
membentuk aspek moral, spirit, dan etos sosial pada anak. Oleh sebab itu
pendidik merupakan figur terbaik dalam hal pandangan anak, yang tindak
tanduk, sopan santunnya, disadari atau tidak akan ditiru anak.
Dalam hal ini al-‟Imᾱm al-Ghᾱzalī berpendapat, pada sebuah
kitabnya Ihyᾱ ‟Ulūmuddīn bahwasannya mensejajarkan para pendidik
dengan deretan para Nabi, sebagaimana yang artinya adalah:
“Makhluk Allah yang paling utama di atas bumi adalah manusia
yang paling utama adalah hatinya. Sedangkan seorang pendidik
sibuk memperbaiki, membersihkan, menyempurnakan dan
mengarahkan hati agar selalu dekat kepada Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā. Maka mengajarkan ilmu adalah ibadah dan pemenuhan
khalifah Allah, bahkan merupakan tugas kekhalifahan Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā yang paling utama.”
B. Makna Dasar Keteladanan
Setiap manusia pada dasarnya diberikan oleh Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā itu kemampuan berpikir (akal) dalam hal meniru atau mengikuti
suatu tindakan, khususnya teruntuk anak kecil yang sangat perlu adanya
arahan dan bimbingan dalam suatu perbuatan. Sebab anak kecil akan
melihat dan mengamati segala bentuk dari sikap perilaku, perbuatan, dan
tindakan ketika apa yang dia temui.
Adapun yang diajarkan dalam Islam, dari sebuah peletak manhaj
langit yang memiliki sebagai mukjizat bagi hamba-hamba pilihan-Nya.
Seperti Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah langit
kepada umat yang memiliki suatu yang disifati dengan kesempurnaan
jiwa, akhlak dan akal yang tinggi, sebab orang-orang dapat menjadikannya
suatu rujukan, mengikutinya, belajar, serta dapat mencontohnya dalam
kemuliaan dan ketinggian akhlak. Karena itu Allah Subḥānahu wa ta‟ālā
mengutus Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm untuk menjadi
23
keteladanan yang baik sepanjang sejarah untuk muslimin dan seluruh umat
manusia.12
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā berfirman:
ى ى كىاليػىوـى الهخرى كىذىكىرى الله لىقىد كىافى لىكيم ف رىسيوؿ الله ايسوىةه حىسىنىةه لمىن كىافى يػىرجيوا اللهثيػرنا كى
Sesungguhnya telah ada pada (diri) ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm itu
suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak
menyebut Allah.” (Qs. al-Aḥzāb/ 33: 21).13
Pada ayat tersebut Allah Subḥānahu wa ta‟ālā memberikan contoh
istimewa kepada Nabi Muhammad, yaitu suatu gambaran sempurna
tentang manhaj dalam metode Islam. Agar bertujuan untuk menjadikan
suatu gambaran hidup yang kekal dengan keagungan pada kesempurnaan
akhlaknya bagi setiap generasi-generasi setelahnya.14
Mengenai penjelasan pada ayat tersebut juga tentang suatu bukti
yang jelas bahwa Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm sebagai
pendidik memberikan teladan nyata kepada para sahabat pada saat perang
Aḥzāb. Ketika perang Aḥzāb juga Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm, memberikan contoh keteguhan dan kekuatan dalam kebaikan.
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm ketika itu menggali parit dengan
cangkul serta mengangkut debu dan tanah dengan alat pikul.15
12
‟Abdūllah Nᾱshiḥ ‟Ulwᾱn, Pendidikan Anak dalam Islam (Solo: Insan Kamil,
2013), 516. 13
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an Kemenag (Jakarta: Departemen Agama,
2009), 420. 14
‟Abdūllah Nᾱshiḥ ‟Ulwᾱn, Pendidikan Anak dalam Islam, 517. 15
Sayyid Qutb, Tafsir Fī Zhilᾱlil Qur‟an, jilid ke 9 (Jakarta: Gema Insani, 2003),
240.
24
Suatu hal teladan yang diajarkan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm kala itu dapat dipastikan adanya kekuatan yang muncul dalam jiwa
para sahabat melihat kesungguhan rasul-Nya. Tentunya adalah hal yang
dapat membawa kesemangatan tinggi sebab dapat berpengaruh ke dalam
jiwa-jiwa kaum muslimin. Oleh karena dengan kekuatan keimanan mereka
juga mewarnai jiwa kaum muslimin lainnya akan pentingnya suatu
semangat, untuk rela berkorban, yakin dan memiliki jiwa yang perkasa.
Tentunya juga Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm seorang
pemimpin dan pendidik yang memberikan contoh dalam suatu perbuatan
nyata seperti suatu bentuk perintah kepada para sahabatnya dalam
bersungguh-sungguh menggali parit sebagai benteng pertahanan kaum
muslimin. Adapun hal itu yang seharusnya pendidik mencontohkan sikap
nyata dalam menjalankan kebaikan. Tetapi bukan sebaliknya memberikan
perintah dan instruksi belaka. Dengan diiringi dengan sikap langsung dan
bersegera dalam menjalankannya. Karena sebab itu dapat berujung dengan
suatu kemalasan dan sikap acuh seorang anak saat ketika mendengar
kebaikan. Oleh sebab itu orang tuanya sebagai pendidik dapat
mengamalkan secara langsung dengan perbuatan.
Dalam sebuah pendidikan Islam yang bersumber pada al-Qur‟an dan
Sunnah Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm, metode keteladanan
tentunya didasarkan kepada kedua sumber tersebut. Sebab pada al-Qur‟an
juga mengenai keteladanan dapat diistilahkan dengan kata „uswah, kata ini
hanya ada di beberapa ayat seperti halnya :
ى لىقىد كىافى لىكيم ف رىسيوؿ الله ايسوىةه حىسىنىةه ل ى كىاليػىوـى الهخرى كىذىكىرى الله مىن كىافى يػىرجيوا اللهثيػرنا كى
”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
25
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia
banyak menyebut Allah.” (Qs. al-Aḥzāb / 33: 21)16
ابػرهىيمى كىالذينى مىعىو قىد كىانىت لىكيم ايسوىةه حىسىنىةه ف ؤيا اذ قىاليوا لقىومهم ان بػيرىءه
ءي منكيم كىما تػىعبيديكفى من ديكف الله اكىةي كىالبػىغضىا نىكيمي العىدى نػىنىا كىبػىيػ ا بػىيػ كىفىرنى بكيم كىبىدى
ا حىته تػيؤمنػيوا بلله كىحدىه اىبىدن ىستػىغفرىف لىكى كىمىا اىملكي ال قػىوؿى ابػرهىيمى لىبيو لىنىا كىالىيكى المىصي رىبػنىا عىلىيكى تػىوىك لىكى منى الله من شىيءو لنىا كىالىيكى اىنػىبػ
“Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrāhīm
Alaīhi al-salām dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika
mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri
dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami
mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu
ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu
beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrāhīm Alaīhi al-
salām kepada ayahnya, ”Sungguh, aku akan memohonkan ampunan
bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah
terhadapmu.” (Ibrāhīm Alaīhi al-salām berkata), “Ya Tuhan kami,
hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau
kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali”, (Qs. al-
Mumtaḥanah/ 60: 4)17
ى كىاليػىوـى الهخرى لىقىد كىافى لىكيم فيهم ايسوىةه حىسىنىةه لمىن كىافى يػىرجيوا كىمىن يػتػىوىؿ فىاف اللهى ىيوى الغىن احلىميدي الله
“Sungguh, pada mereka itu (Ibrāhīm Alaīhi al-salām dan umatnya)
terdapat suri teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang
mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian,
dan barangsiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang
Maha kaya, Maha Terpuji.” (Qs. al-Mumtaḥanah/ 60 : 6) 18
Dari ayat tersebut juga nampak sebuah kata “„uswah” yang selalu
digandengkan dengan sesuatu hal yang baik “ḥasanah” tentunya dapat
digambarkan suatu hal yang baik.
16
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 614. 17
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 810. 18
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 811.
26
Karena Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm sebagai pembawa
risalah Islam juga sebagai teladan yang baik bagi umatnya. Nabi
Muhammad, dalam berbagai kesempatan selalu terlebih dahulu
mempraktikkan semua ajaran yang disampaikan Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā, sebelum menyampaikan kepada umatnya. Sehingga tidak ada celah
bagi orang-orang yang tidak senang untuk membantah atau menuduh
bahwa Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm, hanya pandai bicara saja.
Ada pun kata sebuah “uswah” juga menjadi suatu pemikat, umat muslim
yang menjauhi semua larangannya disampaikan dengan mengamalkan
semua tuntutan yang diperintah oleh Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm, seperti halnya dalam melaksanakan suatu perintah seperti shalat,
puasa, nikah, dan lain-lainya.19
C. Macam-macam Keteladanan
Abdurrahman al-Nahlawi telah mengemukakan bahwa pola
pengaruh keteladanan berpindah kepada peniru melalui beberapa bentuk,
dan yang paling penting ada dua hal, yaitu pemberian pengaruh
keteladanan langsung yang tak disengaja, dan pemberian pengaruh
keteladanan langsung yang disengaja.
a. Pemberian Pengaruh Secara Langsung
Menurut Abdurrahman al-Nahlawi juga bahwa menjelaskan suatu
pengaruh tersirat terhadap keteladanan yang mana akan menjadikan
tindakan pada seseorang. Oleh sebab itu memiliki suatu sifat yang dapat
mendorong orang lain supaya meniru dirinya, tentunya dalam keunggulan
ilmu pengetahuan, kepemimpinan, atau pun ketulusan sebagainya. Pada
setiap kondisi yang demikian itu, karena terjadi secara langsung tanpa
19
Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, cet 1 (Jakarta:
Balai Pustaka 1995), 117-119.
27
disengaja dan ini berarti bahwa setiap orang dapat memiliki suatu yang
dijadikan panutan oleh orang lain. Tentunya harus senantiasa mengontrol
perilakunya, dan menyadari bahwa dia akan diminta pertanggung jawaban
di hadapan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā atas suatu perbuatan yang diikuti
atau ditiru oleh orang-orang yang mengaguminya.20
b. Keteladanan secara sengaja
Dalam suatu pengaruh keteladanan hal langsung yang disengaja,
contohnya; seorang pendidik menyampaikan suatu bentuk bacaan yang
diikuti oleh anak didiknya, oleh seorang imam tersebut membaguskan
shalatnya untuk mengajarkan shalat yang sempurna. Suatu Ketika
berjihad, ada seorang panglima perang yang muncul di depan barisan
untuk menyebarkan pengaruh ruh keberanian, serta pengorbanan yang
tampil ke garis depan dalam diri para tentara. Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm telah menggunakan sebuah teknik keteladanan langsung
tersebut dalam berbagai kesempatan. Pada saat Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm dalam mengajarkan shalat kepada kaum Muslim, beliau
naik ke tempat yang tinggi sehingga bisa terlihat oleh semua orang.
Kemudian Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm bersabda yang artinya
itu:
“Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku bahkan bisa dikatakan,
seluruh kehidupan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm adalah
penjelasan terhadap syariah Islam. Maka ketika Aisyah r.a. ingin
menerangkan akhlak Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
dengan ungkapan terbaiknya“Akhlaknya adalah al-Qur‟an”21
20
Abdurrahman al-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan
Masyarakat, cet. IV (Jakarta: Gema Insani 2004), 265. 21
M.Rawwas Qal‟ahji, Biografi Nabi Saw “Menyibak Tabir Kepribadian Rasul
Muhammad Saw” (Dharan: Mahabbah Pustaka, 1986), 168.
28
Berbagai contoh praktis keteladanan dalam perilaku-perilaku mulia yang
diterapkan kepada anak-anak, dalam kehidupan dan pertumbuhannya di
antaranya sebagai berikut:
a. Mendidiknya agar terbiasa berwudhu setiap kali bangun tidur, dan
bukan hanya mencuci muka saja.
b. Mendidiknya agar terbiasa tidur segera setelah shalat isya. Tidak
boleh dibiarkan terlambat tidur agar anak bisa bangun tepat waktu
shalat shubuh.
c. Mendidiknya agar terbiasa menerima tamu.
d. Melatihnya agar bisa berbelanja berbagai kebutuhan rumahnya.
e. Membiasakannya untuk berjamaah shalat di masjid tepat pada
waktunya.
f. Bila memiliki anak perempuan, maka harus dibiasakan untuk
memakai hijab.
g. Membiasakan untuk melakukan puasa sunnah.
h. Membiasakan untuk makan dan minum dengan tangan kanan.22
Hal yang dapat memberikan suatu keteladanan dalam setiap proses
pendidikan anak, maka sepatutnya seorang pendidik memperhatikan
kelebihan dan kekurangannya ketika pada metode pendidikan tersebut itu.
Pada setiap penerapannya yang dijalankan dengan pertimbangan yang
baik. Tentunya orang tua juga akan sangat berhati-hati dalam memberikan
suatu percontohan dalam kehidupan sehari-hari. sebab tingkah lakunya
tersebut dapat dilihat dan diperhatikan anak. Di antara kelebihan metode
keteladanan, adalah:
22
Muhammad sa‟id Mursi, Melahirkan Anak Masya Allah, cet. I ( Jakarta:
Cendikia, 2001), 142.
29
1. Supaya dapat membiasakan seorang anak didik dalam
mengajarkan suatu ilmu yang dipelajarinya.
2. Perlu mencontohkan untuk seorang pendidik dalam mengevaluasi
hasil dalam belajarnya.
3. Tentunya tujuan seorang pendidikan juga harus terarah serta
tertuju dengan maksimal yang baik.
4. Tentunnya keteladanan juga pada suatu lingkungan di sekolah,
keluarga maupun dimasyarakat harus baik, maka akan tercipta
situasi yang baik bagi seorang anak.
5. Dengan adanya hubungan harmonis antara pendidik dan peserta
didik.
6. walau tidak langsung seorang pendidik memperoleh dalam
menerapkan sebuah ilmu yang diajarkannya.
7. Sikap semangat pengajar juga yang akan mendorong supaya
berbuat suatu kebaikan yang akan dicontoh.
Adapun suatu dari kekurangan dalam metode keteladanan ke satu,
karena sikap yang dicontoh tidak baik, maka cenderung untuk
mengikutinya tidak baik. Ke dua, sebab teori tanpa praktek akan
berdampak kepada verbalisme. Suatu pengajaran anak dalam Islam
tentunya hal yang sangat penting begitupun dalam lingkungan keluarga,
karena suatu pengasuhan dan bimbingan orang tua terhadap anak didiknya
dapat menyebabkan untuk memulai belajar, meniru dan mengamati
perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya. Untuk menjadikan suatu
panutan bagi dirinya, sebab pada anak belum awalnya belum tentu
terbentuk hal kemandiriannya dalam berpikir dan bersikap sehingga anak
tersebut akan tumbuh dewasa.
30
Adapun dari Dr. Nashih Ulwan menurutnya dalam buku pendidikan
anak dalam Islam. Beliau menyebutkan macam-macam keteladanan dari
seorang pendidik yang disandarkan kepada Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm suatu teladan dalam segala aspek kehidupan di antara
keteladanan dalam suatu ibadah, akhlak, kedermawanan, zuhud, tawadhu,
pemaaf dan kemurahan hati, kecerdasan bersiasat, kekuatan fisik, siasat
yang cerdik, serta keteguhan memegang prinsip.23
c. Keteladanan dalam ibadah
Suatu sikap teladan Nabi dalam bidang ibadah diriwayatkan dari al-
Mughirah bin Syu‟bah bahwa Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
melakukan shalat malam sampai kaki beliau bengkak. Ketika dikatakan
kepada beliau, bukankah Allah Subḥānahu wa ta‟ālā telah
mengampunimu. Demikian hati Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
selalu terkait dengan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā, beliau sangat
menyenangi ibadah dan bermunajat. Bangun di malam hari untuk shalat,
beliau menempati kedudukan tertinggi dalam ibadah dan melakukan
semua perintah Allah Subḥānahu wa ta‟ālā berupa tahajud, ibadah, tasbih,
dzikir dan doa. Menghiasi diri dengan amalan-amalan sunnah
sebagaimana firman Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dalam al-Qur‟an:24
فلىةن لكى كىمنى اليل فػىتػىهىجد بو ل اىف يػبػعىثىكى رىب كى مىقىامنا مميودنا عىسه نى“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhanmu
mengangkatmu ke tempat yang Terpuji. (Qs. al-Isrā„/ 17: 79)25
Adapun halnya dalam sikap teladan orang tua suatu hal kebiasaan
bagi anaknya untuk melaksanakan ibadah, sebab seorang anak dapat
23
‟Abdūllah Nᾱshiḥ ‟Ulwᾱn, Pendidikan Anak dalam Islam, 518. 24
‟Abdūllah Nᾱshiḥ ‟Ulwᾱn, Pendidikan Anak dalam Islam, 519-520. 25
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 405.
31
mengamati sikap orang tuanya serta cenderung akan mengikuti aktivitas
orang-orang dewasa disekitarnya .
d. Keteladanan Dalam Berakhlak
Suatu hal Keteladanan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm
adalah berakhlak serta memiliki hubungan dari setiap akhlak beliau yang
mulia sebagai berikut:
1. Karena Keteladanan kedermawanan akan tampak dari suatu pribadi
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm seperti halnya dalam
memberi tanpa akan takut miskin.
2. Keteladanan pada sifat zuhud, seperti halnya Abdullah bin Mas‟ud
r.a berkata, aku masuk menjumpai Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm ketika beliau telah tidur di atas selembar tikar yang
nampak di badan beliau yang mulia.
Adapun menurut Ibnu Jarir telah meriwayatkan bahwa Aisyah
berkata, Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm tidak pernah merasakan
kenyangnya sepotong roti gandum selama tiga hari berturut-turut
semenjak beliau datang ke Madinah sampai beliau meninggal dunia.
kehendaki.
Karena Keteladanan seorang pengajar yang diajarkan oleh
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm dalam suatu sifat zuhud
bukanlah berarti Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm itu miskin serta
tidak memiliki makanan. Semestinya beliau ingin hidup mewah,
bergelimangan kesenangan dunia beliau bisa melakukannya. Dunia itu
pasti datang tunduk patuh kepadanya. Akan tetapi sebaliknya jika beliau
menghendaki kehidupan yang zuhud dan menahan diri, karena beberapa
tujuan berikut :
32
a. Suatu pembelajaran mengenai makna tolong menolong dengan
sepenuh hati dan untuk mementingkan orang lain.
b. Sebab Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm karena
keinginannya bahwa generasi setelahnya mengikuti kehidupan
yang sederhana.
c. Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm pembelajaran
terhadap orang-orang munafik, kafir dan yang memusuhi
Islam bahwa beliau mengajak manusia bukan untuk
menumpuk harta, melainkan hanyalah membawa pahala dari
Allah semata.
e. Keteladanan dalam sifat tawadhu
Ketika orang-orang yang sezaman bersama Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm bahwa beliau akan selalu memuliakan salam kepada para
sahabatnya, dan selalu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang
yang berbicara kepadanya. Sebagaimana firman Allah:
ن اتػبػىعىكى منى الميؤمنيى نىاحىكى لمى كىاخفض جى“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,
Yaitu orang-orang yang beriman. (Qs. al-Syu‟arā / 26 : 215)26
f. Keteladanan Dalam Sifat Pemaaf Dan Kemurahan Hati
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm telah mencapai tingkat
tertinggi dari sifat pemaaf dan kerendahan hatinya. Oleh sebab itu beliau
melawan orang-orang Arab yang sifatnya kasar, namun dengan
kerendahan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm disaat
memperlakukan orang yang telah memarahinya tetapi beliau mendapatkan
26
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 245
33
kemenangan, karena dari perlakuan beliau itu, terhadap penduduk Mekah
yang sangat menyakiti, ketika menindas sampai mengusirnya dari
Negerinya sendiri, serta telah menuduh sampai mengatakan kebohongan
dan kepalsuan bahkan berniat akan membunuh rasul, namun dengan
kemurahannya beliau itu nampak ketika penaklukan kota Mekah, saat
pasukan kaum muslimin sudah memenuhi Mekah, karena dengan sifat
pemaaf serta pemurah rasul itu meliputi seluruh penduduk Negeri. Sebab
kebiasaan para pemimpin di muka bumi yang akan membunuh musuh-
musuh yang telah merugikannya, namun apa yang dilakukan seorang
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm ketika mengumpulkan mereka
dengan keamanan lalu mengatakan “pergilah, kalian bebas”. Tentu tidak
mungkin beliau sampai mencapai derajat tertinggi dari suatu sifat
kemurahan hatinya , sedangkan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā telah
menurunkan ayat-Nya:
خيذ العىفوى كىأمير بلعيرؼ كىاىعرض عىن الههليى “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Qs. al-
A‟rāf / 8 : 199).
g. Keteladanan Dalam Bersiasat
Karena dengan keteladanan Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm tentang suatu kecerdasannya itu dalam bersiasat. Sebab beliau
menjadi sebuah teladan pada siasatnya yang cerdik untuk semua kalangan
baik mereka yang beriman kepadanya dan yang tidak, namun jika Nabi
Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm tidak disifati dengan suatu
34
kecerdasan bersiasat yang Allah Subḥānahu wa ta‟ālā menganugerahkan
untuknya nabi pastilah beliau tidak dapat mampu dalam menegakan
negara Islam di Madinah, dan juga tidak akan mampu membuat
semenanjung Arab datang kepada beliau untuk menunjukan kecintaan dan
loyalitas mereka, tentu mungkin beliau tidak menjadi teladan yang baik
dalam bersiasat dan berinteraksi, sedangkan beliau menjadi pelaksana dari
Tuhannya untuk bersiasat dan berinteraksi dengan sempurna. Perintah
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā kepada Nabi berikut ini:
نى الله لنتى نػفىض وا من حىولكى لىيم فىبمىا رىحىةو م كىلىو كينتى فىظا غىليظى القىلب لىى فىاذىا عىزىمتى فػىتػىوىكل عىلىى الله فىاعفي عىنػهيم كىاستػىغفر لىيم كىشىاكرىيم ف الىمر اف الله
ب الميتػىوىكليى يي“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepada-Nya. (Qs. Āli- Imrān / 3: 159)
h. Keteladanan Memegang Prinsip
Karena dengan keteladanan seorang Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm memegang prinsip, karena memang sifat tersebut adalah salah
satu akhlak yang mulia. Dalam keteguhan hati pamannya itu mungkin
yang akan menyerahkan kepada kaum Quraisy dan menelantarkannya. lalu
mengatakan sebagai pengemban risalah Islam yang abadi untuk
menunjukan kepada dunia, bagaimana seharusnya teguh memegang
keyakinan.
35
“Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan
matahari di tangan kananku, dan bulan ditangan kiriku, aku tidak
akan pernah meninggalkan dakwah ini, Aku tidak akan
meninggalkan sampai Allah menjadikannya menang atau aku binasa
karenanya.”27
Lalu temannya itu berdiri sambil menangis tersedu-sedu, melihat
tekadnya yang kuat dan keteguhannya dijalan dakwah sampai tidak peduli
apapun yang terjadi, sang paman berkata, “pergilah wahai anak
saudaraku”,katakanlah apa yang ingin engkau katakana , demi Allah, aku
tidak akan pernah menyerah kamu selamanya.
27
Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, 518.
37
BAB III
BIOGRAFI
A. Profil Buya Hamka
Hamka adalah julukan dari seorang penafsir indonesia, ia dibawa ke
dunia di sebuah kota Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908.
Hamka juga seorang sastrawan Indonesia, sama seperti ulama‟ dan latihan
politik juga. dia mungkin pergi ke sekolah kota hanya, selama tiga tahun
sekolah ketat sebelumnya di Padang Panjang dan Parabek bukittinggi
untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari itu, dengan berkat ini, ia
dalam bahasanya dapat mendominasi bahasa Arab, yang dapat memiliki
pilihan untuk melihat secara umum tulisan Arab, termasuk interpretasi dan
komposisi barat. Mengikuti yayasan Muhammadiyah dimulai pada tahun
1928 dalam pandangan panjang. Awal tahun 1928, ia mengetahui tentang
cabang Muhammadiyah di padang panjang.
1. Riwayat Hidup Hamka
Haji Abdul Malik Karim Amrullah juga seorang sastrawan
Indonesia, Hamka menemukan julukan seperti Buya, itulah hal yang
tersirat dari seruan individu Minangkabau yang mendapat dari kata ayah,
abuya dalam metode Arab ayahku, atau individu yang dihormati. Ayahnya
juga adalah seorang Syekh Abdul Karim Amrullah, yang dikenal sebagai
Haji Rasul, yang merupakan pelopor Pembangunan Islah (tajdid) di
Minangkabau, setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906.1
Buya Hamka juga merupakan individu otodidak (terlatih sendiri) di
berbagai bidang sains seperti cara berpikir, menulis, sejarah, humanisme
dan masalah legislatif, baik Islam maupun Barat. Dengan kemampuan
1 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem
Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009), 349.
38
Arabnya yang tinggi, ia memiliki pilihan untuk penelitian yang dibuat oleh
peneliti dan seniman Timur Tengah yang signifikan, misalnya, Zaki
Mubarak, Jurji Zaidan, „Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan
Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana
Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James,
Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre
Loti.2
Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di
Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang panjang
pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas
Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Padang panjang dari tahun
1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor
Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo,
Jakarta dan tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai
Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan
jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai
negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi).
Hamka merupakan sosok dari sebuah tokoh-tokoh pergerakan,
ketika Hamka masih muda, juga telah melihat mendengar langsung
pembahasan pemulihan dan pengembangan dari ayahnya dan sahabat
ayahnya. Pada usia muda Buya Hamka dinyatakan disebut gelandangan
atau tidak ada arah tujuan. Ayahnya bahkan memanggilnya “Si Bujang
Jauh”. Pada 1924, dalam pada usia 16 tahun, ia pergi ke Jawa untuk
mempertimbangkan latihan tentang perkembangan Islam lanjutan kepada
H. Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (Pengurus
2 Hamka, Kenang-kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 24.
39
Muhammadiyah 1944-1952), RM. Surjopranoto (1871-1959), KH.
Fakhruddin (ayah KH. Abdur Rozaq Fakhruddin) pergi ke kursus
pengembangan di Abdi Dharma Bekerja di Kecamatan Yogyakarta.
Setelah beberapa waktu di sana, Hamka pergi ke Pekalongan dan bertemu
saudaranya dengan pernikahan, A.R. Sutan Mansyur, sekitar saat itu ia
adalah pimpinan Muhammadiyah dari cabang Pekalongan. Di kota itu
Hamka berkesempatan mengenal tokoh-tokoh lingkungan
Muhammadiyah. Pada Juli 1925 Hamka kembali ke Padangpanjang dan
dibantu membangun Tabligh Muhammadiyah di rumah ayahnya di
lapangan, Padangpanjang. Sejak saat itu ke depan Hamka muda mulai
bekerja dalam sebuah komunitas Muhammadiyah.
Dari perjalanan pendidikannya yang sangat singkat dapat diketahui
bahwa Hamka memiliki semangat otodidak yang tinggi. Latar belakang
kehidupannya yang nakal, cepat berubah ketika ia sadar hingga kemudian
mampu mengubah jalan hidupnya yang suram terarah menjadi sosok yang
perlu diteladani. Tercapainya hal ini tidak terlepas dengan peranan tokoh-
tokoh yang meng-ilhami pemikirannya, karena dari merekalah Hamka
mendapatkan pencerahan tentang konsep agama diluar yang selama ini
dipahami sehingga ia dapat menerapkan ilmu-ilmu yang lebih mempunyai
kecenderungan pandangan kepada peperangan terhadap keterbelakangan,
kebodohan, dan kemiskinan.
Hamka mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925
untuk melawan khurafat, bid„ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang
Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di
Padang Panjang. Pada 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah
Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua
Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi
40
Muhammadiyah, menggantikan S.Y Sutan Mangkuto pada 1946. Ia
menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31
Yogyakarta pada 1950.3
Latihan politik Buya Hamka pada tahun 1925, ketika ia masih
menjadi individu dari kelompok ideologi Islam Sarekat. Pada tahun 1945,
untuk membantu melawan kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia.
Jika terjadi wacana dan pergi dengan latihan gerilya di backwoods di
Medan. Pada tahun 1947, Buya Hamka ditunjuk sebagai Direktur Front
Perlindungan Publik Indonesia.
Dan pada tahun 1955 Buya Hamka masuk Konsitusi melalui dengan
partai Masyumi dan menjadi pembicara utama dalam pilihan raya umum.
Pada masa itulah pemikiran Hamka yang sering bertentangan dengan
kerasnya sebuah politik tersebut. Dan adapun ketika partai-partai tersebut
beraliran nasionalis dan komunis yang berkeinginan untuk Pancasila
adalah sebagai dasar negara. Dalam wacana di Konstituen Kumpul-
kumpul, Hamka untuk mengusulkan undang-undang pokok tentang
Pancasila termasuk kalimat komitmen untuk melakukan syariat Islam,
bagi para pengikutnya sebagaimana terkandung dalam perjanjian Jakarta.
Terlepas dari itu, alasan Hamka dengan tegas disyaratkan oleh sebagian
besar individu dari Pertemuan Konstituen, termasuk Presiden Soekarno.
Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh
Presiden Soekarno karena dituduh mendukung Malaysia. Semasa
dipenjarakan, beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar yang merupakan karya
ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai
anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota
3 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan
Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 227.
41
Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan
Nasional Indonesia. Pada tahun 1978, Hamka lagi-lagi berbeda pandangan
dengan pemerintah. Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Daoed Joesoef untuk mencabut ketentuan libur selama puasa
Ramadhan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Perjalanan
politiknya bisa dikatakan berakhir ketika Konsitusi dibubarkan melalui
Dekrit Presiden Soekarno pada 1959. Masyumi kemudian diharamkan
oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Meski begitu, Hamka tidak
pernah menaruh dendam terhadap Soekarno.
Idealisme Hamka kembali diuji ketika tahun 1980 Menteri Agama
Alamsyah Ratu prawira negara meminta MUI mencabut fatwa yang
melarang perayaan Natal bersama. Sebagai Ketua MUI,7 Hamka langsung
menolak keinginan itu. Sikap keras Hamka kemudian ditanggapi
Alamsyah dengan rencana pengunduran diri dari jabatannya. Mendengar
niat itu, Hamka lantas meminta Alamsyah untuk mengurungkannya. Pada
saat itu pula Hamka memutuskan mundur sebagai Ketua MUI.4 Hamka
juga pernah menjadi pengawas Majalah Pedoman, Panji Masyarakat, dan
majalah Gema Islam. Hamka juga menyampaikan karya-karya masuk akal
Islam dan karya-karya menarik seperti buku dan cerpen. Karya masuk akal
yang paling penting adalah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan di antara buku-
bukunya yang memperoleh pertimbangan umum dan berubah menjadi
bahan bacaan abstrak di Malaysia dan Singapura termasuk Tenggelamnya
Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Keamanan Ka‟bah, dan Merantau Ke
Deli. Serta dinamis dalam masalah ketat dan politik, Hamka adalah
seorang penulis, esais, dan pengorbit. Sejak 1920-an, Hamka telah
4 M. Yunan Yusuf, Corak Pemikiran kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas
Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam (Jakarta: Permadani, 2003), 54.
42
menjadi penulis untuk beberapa surat berita, misalnya, Pelita Andalas,
tangisan Islam, bintang, dan kemajuan Muhammadiyah. Pada tahun 1928
ia berubah menjadi manajer editorial penghibur majalah The
Advancement Society. Pada tahun 1932, ia menjadi berwenang dan
mendistribusikan majalah al-Mahdi di Makassar.
2. Intelektual Hamka
Hamka juga merupakan sosok yang berfungsi dalam segala
pembangunan, misalnya, di bidang agama dan sosial dan politik, dalam isu
pemerintahan Hamka dimulai pada tahun 1925 ketika ia berubah menjadi
individu dari kelompok ideologis Sarekat Islam Pada tahun 1947, Hamka
terpilih sebagai eksekutif Front Perlindungan Publik Indonesia. Selain
dinamis dalam isu ketat dan politik, Hamka adalah seorang penulis,
pengarang, pengawas dan penyalur. Sejak tahun 1920-an, Hamka telah
menjadi penulis untuk beberapa makalah, seperti Pelita Andalas, Seruan
Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, ia
menjadi manajer majalah The Advancement Society. Pada tahun 1932, ia
menjadi manajer editorial dan mendistribusikan majalah al-Mahdi di
Makassar. Hamka juga telah menjadi Pahlawan majalah Pedoman
Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.
Pada tahun 1949 Hamka diakui sebagai jurnalis untuk koran
Merdeka dan majalah Pemandangan. Kemudian dalam isu-isu
pemerintahan praktis ia memasuki keputusan politik secara keseluruhan
pada tahun 1955 dan Hamka dipilih untuk membentuk konsitusi dari
Pertemuan Masyumi. Dalam organisasi, yang sesuai pengaturan Masyumi,
43
Hamka mendekati dengan dalilnya untuk membangun negara tergantung
pada al-Qur'an dan Sunah.5
Pada pertemuan negara-negara Islam di Rabat (1968), dewan masjid
di Mekkah (1976) juga angkatan tentang Islam dan kemajuan manusia di
Kuala Lumpur Malaysia Selama Permintaan Baru, Hamka sering berbagi
kepada lembaga publik untuk pergi ke pertemuan bangsa-bangsa Islam.
Hamka yang tercatat sebagai pengurus Silaturahmi Ulama Indonesia.
Persetujuannya karena kontras dalam wawasan di antara MUI dan
otoritas publik tentang perayaan Natal dengan umat Kristen dan Muslim.
pada jam berkumpul di antara MUI dan otoritas publik, Ulama Masalah
Ketat yang saat itu dijabat oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara mengambil
langkah untuk hengkang sebagai Pendeta Agama jika MUI tidak
mengingkari fatwa tersebut.
Terlepas dari itu, Hamka memikirkan bahwa Imam Usaha Ketat
tidak perlu pergi, dengan alasan MUI akan menyangkal fatwa tersebut
dengan catatan bahwa disavowal fatwa tersebut bukan berarti menjatuhkan
legitimasi fatwa yang telah diberikan.6 MUI menganggap haram bagi umat
Islam untuk pergi ke perayaan Natal bersama dengan orang-orang Kristen,
sementara otoritas publik mempertimbangkan dalam hal apapun. Pada usia
73 tahun, Hamka tercatat sebagai sosok yang luar biasa yang telah
berkontribusi besar bagi negara dan negara Indonesia, khususnya muslim
Indonesia. Baik sebagai pekerjaan yang berfungsi di mata publik maupun
sebagai karya logis yang memiliki nilai tinggi.
5 Yunan Yusuf, Corak Pemikiran, 51. Lihat juga, Ahmad Syafi‟I Ma‟arif, Peta
Bumi Intelektualisme Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1993), 197. 6 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1983), 195.
44
3. Pandangan Ulama Terhadap Hamka
Cara pandang Ulama mengenai sosok Hamka adalah mereka yang
berpendapat suatu pandangan yang sangat baik yaitu dia dikenal sebagai
seorang ulama yang independen, sudah terbukti di saat Hamka pertama
kali datang ke Jakarta beliau seorang yang sangat ramah, serta akrab
dengan anak muda dan tiada jarak dengan masyarakat mengenai dari kisah
sejarah Masjid Agung
Perspektif ulama tentang sosok Hamka adalah individu yang
berpikir pandangan yang sangat baik bahwa ia dikenal sebagai pendeta
bebas, telah ditunjukkan ketika Hamka awalnya datang ke Jakarta ia
adalah seorang yang dibuang dengan baik, dan berkenalan dengan anak-
anak dan tidak ada pemisahan dari daerah setempat tentang dari kisah
masjid al-Azhar7 Kebayoran Baru Jakarta. Hamka pada saat itu pindah ke
Jakarta untuk dimintai nasehat oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI),8 mana
yang akan dibangun terlebih dahulu. gedung sekolah atau masjid,
mengingat aset sangat dibatasi, Dia mendorong, merakit masjid terlebih
dahulu. Hamka kemudian sebagai pelopor, khatib dan Imam Besar Masjid
al-Azhar Fabulous yang awalnya memindahkan latihan masjid yang paling
luas terdampak di negara itu.
Tausiah subuh di Jakarta diprakarsai oleh Masjid Agung al-Azhar.
Seperti diketahui dari sejarah, masjid Al-Azhar berubah menjadi benteng
umat Islam terhadap sosialis/PKI yang perlu menguasai Indonesia sebelum
diperkenalkannya permintaan baru. dari kompleks masjid al-Azhar yang
menakjubkan selesai pada tahun 1957, Hamka memindahkan distribusi
7 Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa Masjid Al-Azhar dengan berbagai
kegiatannya, seperti sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, serta kegiatan Remaja Islam dan
penerbitan Panji Masyarakat, berasal dari tanah wakaf orang-orang NU tetapi tidak
terkelola dengan baik, lalu mengalami “pengambilan hus” sehingga menjadi milik
Yayasan Al-Azhar. 8 Dawam Rahardjo, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa (Jakarta: Mizan,
1993), 201-202.
45
majalah Gema Islam, dan mengendarai majalah Panji Masyarakat sejak
didistribusikan hingga sepi untuk diterima.
Pada titik ketika ia menjadi administrator utama pertemuan Ulama
Indonesia (MUI) dari 1975 hingga 1981. Hamka mengetahui cara
mengarang gambar MUI sebagai landasan bebas dan sah untuk menyikapi
suara umat Islam. Hamka tidak akan mendapatkan santunan sebagai
Pengurus MUI. Imam agama sebelumnya H.A. Mukti Ali mengatakan,
"Landasan MUI adalah dukungannya terhadap negara dan negara. Tanpa
sosok Hamka, pendirian tidak akan memiliki pilihan untuk berdiri.9
Hal yang paling berkesan ketika Hamka mengisi hidupnya sangat
signifikan dalam pertempuran otonomi publik di Sumatera Barat. Selain
itu, pada tahun 1950 Hamka juga dinamis dalam Pertemuan Otoritas
Masyumi. Salah satu pernyataan yang menggambarkan muruah
(ketenangan) sebagai kepala individu, antaralain ketika masalah
pemerintahan menjadi "administrator" sekitar tahun 1950, kata Hamka,
Ada banyak jabatan yang menginginkannya. Dan kursiku adalah milikku
karena tempat kembaliku sendiri adalah orang yang disertai arahan tidak
baik kepada diri sendiri yang perlu mengelola dalam penjagaan.
Sebagai penjaga gerbang kepercayaan diri sendiri, Hamka sebagai
ketua umum MUI, meneruskan kontribusi kepada Presiden Soeharto atas
isu Kristenisasi, dan posisi Presiden sesuai dengan pandangan MUI bahwa
dengan asumsi perlu membuat kesesuaian yang ketat, individu yang
sekarang ketat seharusnya tidak fokus untuk diundangkan ketat lainnya.
Pada pertengahan 70-an Hamka membantu umat Islam untuk
mengingat kesulitan al-Gazwū al-fikrī (perang pemikiran). Sesuai Hamka,
penjajahan jiwa terhubung di pinggul dengan pemusnahan kualitas etika
9 M. Yunan Yusuf, 54.
46
dan budaya di negara-negara Islam. Sekularisasi dan sekularisme adalah
pembayaran tiga uang tunai dengan al-Gazwū al-fikrī yang dikirim oleh
dunia Barat untuk mengatasi dunia Islam, setelah imperialisme politik
dalam struktur yang berbeda membingungkan.10
Menurut pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) K.H A Syaikhu
dalam Hamka di mata hati umat, Hamka menempatkan dirinya bukan
hanya sebagai pimpinan Masjid al-Azhar Fabulous atau asosiasi
Muhammadiyah, namun selain sebagai kepala umat Islam semua dalam
semua, membayar sedikit mengindahkan ke kelas. Sebagai sosok Ulama
Hamka otonom juga dikenal solid dalam standar dan ekskusinya,
Tafsir al-Qur'an bernama Tafsir Al-Azhar, sesuai dengan nama
Masjid Al-Azhar. Hamka tetap konsisten menghasilkan sesuatu karya di
saat matahari terbit, adalah karya terbaik Buya Hamka di antara lebih dari
114 judul buku tentang agama, penulisan, penalaran, Sufism, masalah
legislatif, sejarah dan budaya yang luar biasa sampai 'sampai saat ini.11
Karya-karya Hamka mempunyai gaya bahasa tersendiri yang khas.
Pemahaman tentang tafsir al-Qur'an selesai menyelasaian dengan 30 juz,
dikumpulkan ketika Hamka berada dalam kekuasaan politik sistem
selama lebih dari 2 tahun.
Sehubungan dengan orang lain yang dibebaskan dari tahanan politik
memberikan buku tentang analisis sistem keputusan. Bagaimanapun,
berbeda dengan Hamka, keluar dari penjara menciptakan karya
pemahaman tentang bagian-bagian al-Qur'an. Ketika itu pun secara
terbuka lewat tulisannya memaafkan semua orang yang pernah
menyakitinya saat mereka berkuasa. Lalu mantan Presiden RI pertama Ir.
Soekarno wafat 21 Juni 1970 Hamka bertindak sebagai imam shalat
10
A. Susanto, Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2009), 103-104. 11
Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2000), 78.
47
jenazahnya. Suatu akhlak mulia dan suri teladan bagi bangsa Indonesia.
Menjelang pertengahan 1981 Hamka meletakkan jabatan sebagai Ketua
Umum MUI. Dia berhenti karena mempertahankan prinsip dari pada
mencabut peredaran Fatwa MUI yang menyatakan bahwa mengikuti
upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ulama besar
Hamka wafat di Jakarta 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H) dalam usia
73 tahun.
Buya Hamka, seorang ulama, pemimpin, pujangga, pengarang,
sejarawan, pengabdian, karya dan sumbangannya dalam membangun
kesadaran umat Islam dan cita-cita bangsa tetap dikenang dan menjadi
inspirasi bagi generasi muda masa kini.12
4. Karya-karya Hamka
Adapun Tafsir al-Azhar karya yang paling terkenal di kalangan
masyarakat, namun Buya Hamka juga memiliki banyak memiliki karya-
karya lainnya diantaranya berjumlah 49 karya sebagai berikut :
1. Si Sabariah (roman dalam bahasa Minangkabau), Padang Panjang:
1926.
2. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shidiq) Medan: Pustaka
Nasional,1929.
3. Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Medan Pustaka Nasional, 1929.
4. Laila Majnun, Jakarta: Balai Pustaka, 1932.
5. Salahnya Sendiri, Medan: Cerdas, 1939 .
6. Merantau ke Deli, cet 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977 (ditulis pada
tahun 1939).
7. Keadilan Ilahi, Medan: Cerdas, 1940.
12
Mohammad Damami, Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka (Yogyakarta:
Fajar Pustaka Baru, 2000), 77-180.
48
8. Angkatan Baru, Medan: Cerdas, 1949.
9. Cahaya Baru, Jakarta: Pustaka Nasional, 1950.
10. Menunggu Beduk Berbunyi, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
11. Terusir, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
12. Sejarah Islam di Sumatera, Medan: Pustaka Nasional, 1950 .
13. Mengembara di Lembah Nil, Jakarta: NV. Gapura, 1951.
14. Di Tepi Sungai Dajlah, Jakarta: Tintamas, 1953.
15. Mandi Cahaya di Tanah Suci, Jakarta: Tinta mas 1953.
16. Empat Bulan Di Amerika, 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1954.
17. Di Bawah Lindungan Ka‟bah, Cet. 3, Jakarta: Mega Bookstore,
1957.
18. Di Dalam Lembah Kehidupan (kumpulan cerpen), Jakarta: Balai
Pustaka, 1958.
19. Dijemput Mamaknya, Cet. 3, Jakarta Mega Bookstore, 1962.
20. Tuan Direktur, Jakarta: jayamurni, 1961.
21. Cermin Kehidupan, Jakarta: Mega Bookstore, 1962
22. Dari Perbendaharaan Lama, Medan: M. Arbi, 1963.
23. Adat MinangKabau Menghadapi Revolusi, Jakarta: Tekad, 1963.
24. Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam pada Masa Kini,
Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
25. Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas,
1973.
26. Antara Fakta dan Khayalan Tuanku Rao, cet. 1 Jakarta: Bulan
Bintang, 1974.
27. Muhammadiyah di Minangkabau, Jakarta: Nurul Islam, 1974.
28. Tanya Jawab Islam, Jilid I dan II cet. 2 Jakarta: Bulan Bintang,
1975.
49
29. Margaretta Gauthier (terjemah karya Alexandre Dumas), cet 7,
Jakarta : Bulan Bintan, 1975.
30. Sejarah Umat Islam, 4 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
31. Studi Islam, Aqidah, Syariah, Ibadah, Jakarta: Yayasan Nurul
Iman, 1976.
32. Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Nurul
Islam, 1976.
33. Merantau ke Deli, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977 (ditulis
pada tahun 1939).
34. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, cet. 13, Jakarta: Bulan
bintang, 1979.
35. Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, cet. 8, Jakarta:
Yayasan Nurul Islam, 1980.
36. Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas
1982.
37. Kebudayaan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
38. Lembaga Budi, cet 7, Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.
39. Tasawuf Modern, cet, 9, Jakarta Pustaka Panjimas, 1983
40. Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian,
Jakarta: Yayasan Idayu, 1983
41. Sullam al-Wushul: Pengantar Ushul Fiqih (terjemah Karya Dr. H.
Abdul Karim Amrullah), Jakarta: Pustaka Panjimas 1984
42. Islam: Revolusi Ideologi dan keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1984.
43. Iman dan Amal Shaleh, Jakarta: Pustaka Panjimas,1984.
44. Renungan Tasawuf, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
45. Filsafat Ketuhanan, cet, 2, Surabaya: Karunia, 1985.
46. Keadilan Sosial dalam Islam, Jakarta: Pustaka Antara, 1985
50
47. Tafsir al-Azhar, Juz I sampai Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas,
1986
48. Prinsip-prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1990.
49. Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri, Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1995.
B. Profil Tafsir al-Azhar
Sesuatu yang tahu dan dapat menarik dalam pertimbangan karya
Tafsir sama seperti namanya juga. Mengenai asal usul nama Tafsir al-
Azhar terdapat 2 anggapan yang saling terkait sejauh pemanfaatan nama
al-Azhar untuk pengertiannya. Pertama sebagaimana namanya dapat
diasumsikan dari posisi di mana terjemahan disajikan dan ditunjukkan
terlebih dahulu, khususnya di Masjid Al-Azhar. Kedua sebagai jenis
"pengembalian" untuk gelar istimewa yang diberikan oleh Perguruan
Tinggi al-Azhar. Ini tampaknya adalah judul logis yang paling penting
dari Kairo al-Azhar Mesir. Ustadzah Fakhriyah atau seperti Spesialis
Honoris Causa lebih forte Hamka adalah individu utama di planet ini
untuk mendapatkan gelar dari al-Azhar College Kairo Mesir.13
Itu membuat terpacu pada pencipta al-Azhar sesuai Hamka,
terdampak oleh 2 hal. 1 untuk pendakian minat pemuda zaman generasi
Islam di tanah air Indonesia dan di beberapa daerah berbahasa Melayu
yang perlu mengetahui substansi al-Qur'an akhir-akhir ini. Hal ini
membuat mereka tidak mampu belajar bahasa Arab. 2 untuk bidang
mubalig dakwah yang membutuhkan data ketat dengan sumber padat
13
Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), Juz I, 44.
51
bagian Al-Qur'an, sehingga normal bahwa terjemahan ini dapat menjadi
ajudan untuk mubalig terlepas dari negara yang mulai cemerlang.14
Penyaluran pertama Tafsir al-Azhar disalurkan oleh pendistribusian
Panduan Periode, Perintis H. Mahmud. Cetakan utama saat mengelola,
menyelesaikan distribusi dari juz 1 ke juz 4. Pada saat itu didistribusikan
demikian juga Juz 30 dan Juz 15 kepada Juz 29 oleh Perpustakaan Islam
Surabaya. Terakhir Juz 5 hingga Juz 14 didistribusikan oleh Yayasan
Nurul Islam Jakarta.15
1. Penulisan Kitab Tafsir al- Azhar
Mengenai penulisan Kitab Tafsir yang terbit di Indonesia itu adalah
Tafsir al-Azhar karya Hamka. Tafsir tersebut suatu hal yang dikenal dapat
memberikan Khazanah pengetahuan serta sangat menarik dari sisi
Kebahasaan. Maupun penyajian pemikiran yang di dalamnya secara
sejarah. Sebabnya Agama mempresentasikannya ada pada keragaman
penafsiran yang sangat berat berkaitan dengan latar belakang sejarah dari
beberapa pandangan. Bahkan sering terjadi perdebatan dalam Agama,
misalnya antara kalangan yang berpola pikir yang tidak baik dan yang
berpola pikir baik, tentunya kedua kalangan ini memiliki pola penafsiran
yang berbeda terhadap Agama mereka. Bahkan pada dasarnya Agama
memang sangat membutuhkan penafsiran untuk memudahkan umat dalam
memahami makna pesan tuhan dalam sebuah kitab sucinya (al-Qur‟an).
Pemahaman Tafsir itu yang akhirnya harus membuka kajian konseptual
dan historis. .16
14
Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz I, 4. 15
Yunan Yusuf, Corak Pemikiran, 55. 16
Rikza Chamami, Dalam Studi Islam Kontemporer (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2002), 113.
52
Tafsir al-Azhar suatu karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah
atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Beliau lahir di sebuah desa lebih
dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan bernama
Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, pada
13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 Februari 1908 M.
Sebelum benar-benar memiliki pemahaman tentang pembicaran Al-
Qur'an, seorang mufassir terlebih dahulu untuk memberikan banyak
pembukaan, yang terdiri dari beberapa adalah oleh semua ini adalah:
Pendahuluan, Pandahuluan, al-Qur'an, I'jaz al-Qur'an, Konten Mukjizat al-
Qur'an, al-Qur'an Lafaz dan makna, Menguraikan al-Qur'an, serta Haluan
Tafsir, mengapa dinamakan "Tafsir al-Azhar", dan terakhir hikmah ilahi.
Tafsir, untuk alasan apa disebut "Tafsir al-Azhar", terakhir
kesendirian ilahi. Dalam satu kasus perkenalan, Hamka sebagai aturan
membuat referensi ke beberapa nama yang dianggap patut dipuji untuk
dirinya sendiri dalam peningkatan peneliti dan Islam yang diperiksanya.
Terutama sehubungan dengan nama-nama yang dirujuk mungkin adalah
individu yang membangkitkan untuk setiap karya dan pengabdian yang
dilindungi untuk pergantian peristiwa dan penyebaran ilmu-ilmu Islam,
tanpa terkecuali dari karya tafsirnya. Nama-nama tersebut selain disebut
Hamka sebagai orang-orang tua dan saudara-saudaranya, juga disebutnya
sebagai guru-gurunya. Dari beberapa nama itu antara lain, ayahnya sendiri
yang merupakan gurunya sendiri, Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah,
Syaikh Muhammad Amrullah (kakek), Abdullah Shalih (Kakek
Bapaknya).17
Karya Tafsirnya dimulai dalam pemeriksaan yang diperkenalkan
pada daybreak address oleh Buya Hamka di masjid al-Azhar yang terletak
17
Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: pembimbing Masa,1970) , 40.
53
di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Pada saat itu, masjid itu belum
bernama al-Azhar. Bersamaan dengan itu, Hamka dan K.H. Fakih Usman
dan H.M Yusuf Ahmad, membagikan majalah Panji Masyarakat. Benar-
benar pada saat itu, nama al-Azhar untuk masjid diberikan oleh Syekh
Mahmud Syaltut, Rektor Perguruan Tinggi al-Azhar mengunjungi
Indonesia pada Desember 1960 dalam rangka menjadi lahan al-Azhar di
Jakarta. Adapun penamaan karya Tafsir tersebut, oleh Buya Hamka ialah
dengan nama Tafsir al-Azhar. Hal tersebut berkaitan erat dengan tempat
lahirnya. Nama tafsir tersebut menjadikan suatu hal yang bersejarah
karena Hamka membuat masjid agung al-Azhar tersebut sebab
mengenakan sebuah karya tulisnya itu Tafsir al-‟Azhar.
Adapun terdapat faktor yang mendorong Hamka untuk
menghasilkan karya tafsir tersebut. Sebab itu dinyatakan sendiri oleh
Hamka dalam Pembukaan di kitab tafsirnya. Di antaranya, ia ingin
menanamkan kekuatan pertempuran dan kepercayaan Islam terhadap jiwa
generasi muda Indonesia yang sangat tertarik memahami al-Qur'an, namun
terhalang oleh ketidak mampuan mereka menguasai Ilmu Bahasa Arab.
Kecenderungan Buya Hamka terhadap penulisan komentarnya juga
bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman para pengkhotbah dan
pengkhotbah serta meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan
khotbah yang diambil dalam sumber-sumber Arab.
Mulai pada tahun 1962, kajian Tafsir yang disampaikan di masjid
agung Al-Azhar ini, dimuat pada majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir
tersebut berlanjut sampai terjadi kekacauan politik yang masjid tersebut
telah dituduh menjadi markas “Neo Masyumi” dan “Humanisme”. Pada
tanggal 12 Rabiul awal 1383 H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh
penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada Negara. Penahanan
54
selama 2 tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena beliau
dapat menyelesaikan penulisan karya tafsirnya.18
Penerbitan awal Tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbitan
Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud. Cetekan pertama
merampungkan penerbitan dari Juz 1 sampai Juz ke 4. Kemudian
diterbitkan pula Juz 30 dan 15 sampai Juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya
dan akhirnya Juz 5 sampai 14 diterbitkan oleh yayasan Nurul Islam
Jakarta.
2. Metode Penulisan Tafsir al-Azhar
Dengan karya Hamka ini maka metode yang dipakai adalah metode
Tahlili19
(Analisis) bergaya khas tartib mushaf. Karena metode ini para
mufasir menguraikan makna yang dikandung dalam ayat dan surat pada
al-Qur‟an tersebut dan sesuai dengan urutan terdapat pada mushaf.
Uraian tersebut mencakup dari berbagai aspek yang terkandung
dalam ayat yang diartikan itu adalah: pemahaman kosakata, konotasi,
kalimat, latar belakang ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain (wajar), dan
tidak melupakan apa yang termasuk dari beberapa pendapat yang telah
diberikan kepada penafsiran ayat-ayat ini, baik yang disampaikan oleh
Nabi, Sahabat, maupun tabi'in dan dari juru bahasa lainnya.
Metode penulisan tafsir yang dipakai adalah metode penafsiran ayat
secara berurutan dimulai dari surat al Fatihah sampai kepada surat al-Nas.
Metode ini disebut metode Tahlili. Secara bahasa metode ini bersifat
18
Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, Mengenang 100 Tahun Hamka (Jakarta:
Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2008), 36. 19
Metode tahlīli adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha
menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dari berbagai seginya dengan
memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur‟an sebagaimana tercantum di dalam mushaf.
Lihat: M. Quraish Shihab, 172.
55
analisis. Semua objek penafsiran dikupas secara terperinci dan teratur
(reguler). Adapun metode penulisan yang dilakukan pada saat menafsirkan
adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Menuliskan ayat dan terjemahnya.
2. Menjelaskan makna nama surat dan identitas lainnya seperti
tempat dan waktu turunnya.
3. Menyebutkan Sabab al-Nuzul dari ayat bersangkutan kalau ada.
4. Menyebutkan tafsir al-Qur‟an, hadis dan qaul sahabat dan tabi‟in.
5. Menyebutkan sirah Nabi, sahabat dan para salihin kalau ada.
6. Mengemukakan perbedaan pandangan para mufasir.
7. Mengkorelasikan kandungan ayat dengan konteks pengarang.
8. Membuka pengalaman kehidupan pribadi, orang lain yang ada
korelasinya.20
9. Menyebutkan syair-syair kuno
10. Mengakhirinya dengan kesimpulan serta ajakan untuk
mentadabburinya.21
Terdapat dalam sebuah kata pengantar, Hamka menyebutkan bahwa
beliau memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara Naqli dan Akal
(riwayah dan dirayah). Para penafsir tidak hanya semata-mata mengutip
atau menulis pendapat orang-orang terdahulu, tetapi mempergunakan juga
tinjauan dari pengalaman sendiri dan tidak pula semata-mata menuruti
pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang-
20
Hamka, Tafsir al-Azhar 98. 21
Saiful Amin Ghofur, Profil Mufassir al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan
Madani, 2008), 212.
56
orang terdahulu berarti. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat dari
orang terdahulu berarti hanya suatu riwayat. Sebaliknya, jika hanya
memperturutkan akal sendiri besar bahayanya akan keluar dari garis
tertentu yang digariskan agama, sehingga dengan disadari akan menjauh
dari maksud agama.22
Adapun yang diikuti beberapa komentator adalah tentang sekte salaf,
yaitu Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm dan teman-teman dan
ulamanya yang mengikuti jajarannya. Dalam hal aqidah dan ibadah
semata-mata taslim, artinya menyerah dengan tidak banyak lagi Tanya.
(Dan orang-orang yang menginginkan) dengan al-Qur‟an (menjadi musuh
bagi mereka dan orang-orang yang menginginkan kesyi‟ahan) tidak
diinginkari dalam hal ini. Penulis komentar ini tidak hanya taqlid untuk
pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada
kebenaran untuk diikuti dan meninggalkan yang jauh menyimpang. Tafsir
yang amat menarik ini yang dibuat contoh adalah Tafsir al-Manār karya
Sayyid Rasyid Ridha berdasarkan atas ajaran Tafsir guru Syeikh
Muhammad Abduh.
C. Corak Tafsir al-Azhar
Contoh yang ditetapkan oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah
perpaduan sufi al-Adābī al-Ijtimā‟ī. Contoh ini (masyarakat sosial) adalah
bagian dari pemahaman yang muncul dalam kesempatan saat ini. misalnya
contoh terjemahan yang terlihat memahami tulisan-tulisan al-Qur'an dalam
metode utama mengkomunikasikan arus keluar al-Qur'an dengan hati-hati,
pada saat itu mengungkapkan implikasi yang disinggung oleh al-Qur'an
dengan gaya yang sangat baik dan menarik
22
Hamka, Tafsir al-Azhar (pembimbing Masa: Jakarta, 1970), 36.
57
Pada saat itu seorang mufassir berusaha mengaitkan naṣh yang
dicari dengan realitas sosial dan kerangka sosial yang ada. Sebagaimana
ditunjukkan oleh al-Żahab, apa yang tersirat oleh al-Adābī al-Ijtimā‟ī
adalah contoh terjemahan yang mengklarifikasi bagian-bagian al-Qur'an
tergantung pada kecerdasan artikulasi yang terbentuk dalam bahasa yang
jelas, dengan menekankan alasan prinsip pengungkapan al-Qur'an, dan
setelah itu menerapkannya pada permintaan sosial,
Seperti menyelesaikan permasalahan umat Islam dan bangsa jenis
tafsir ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan mufassir yang
menganggap bahwa selama ini tafsir al-Qur'an hanya didominasi oleh
tafsir yang berorientasi pada nahwu, bahasa, dan perbedaan madzhab, baik
di bidang ilmu kalam, fiqih , Sufi, dan sebagainya, dan jarang ditemukan
dalam bentuk penafsiran yang secara khusus menyentuh inti dari al-
Qur‟an, sasaran dan tujuan akhirnya, secara operasional, seorang mufassir
jenis ini dalam pembahasannya tidak mau terjebak pada kajian pengertian
bahasa yang rumit, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana dapat
menyajikan tafsir al-Qur‟an yang berusaha yang mengaitkan naṣh dengan
realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, yang
secara fungsional dapat memecahkan problem umat.
Ada pun penggagas corak tafsir al-Adābī al-Ijtimā‟ī adalah
Muḥammad „Abduh, tokoh pembaharu terkenal asal Mesir, dengan kitab
tafsir al-Manar yang disusun dengan muridnya Muḥammad Rasyid Ridhā.
Di antara kitab tafsir yang dengan corak al-adābī al-Ijtimā‟ī selain Tafsir
al-Manār adalah Tafsir al-Qur‟an karya syaikh Muḥammad al-Marāgīi,
Tafsir al-Qur‟an al-Karim karya syaikh Maḥmūd Ṡyaltūt, dan Tafsir al-
Wādḥī karya Muḥammad Maḥmūd Ḥijāzī. Sedangkan corak sufinya
banyak diperlihatkan dengan teknis pendekatan terhadap tasawuf yang
58
ditunjukan Hamka. Oleh sebab itu tasawuf Hamka lebih Nampak modern
di dalam menerjemahkan makna Tuhan secara positif.
1. Sistematika Penafsiran Tafsir al-Azhar
Pada sebuah penafsirannya, Hamka membuka tafsir tersebut dengan
beberapa pembahasan hal yang mengenai seperti: definisi al-Qur‟an, isi
mukjizat al-Qur‟an, al-Qur‟an lafaz dan makna, menafsirkan al-Qur‟an,
haluan tafsir alas an pemberian nama Tafsir al-Azhar, dan menguraikan
hikmah ilahi setelah proses penafsiran.
Buya Hamka Mengomentari tentang I‟jaz al-Qur‟an. Menurut Buya
Hamka I‟jaz Nabi yang bersifat zahir (bisa dilihat oleh mata) Seiring
dengan kemajuan zaman sudah menurun keampuhannya dalam
menunjukan ego manusia. Yang tersisa adalah mukjizat al-Quran yang
berlaku sepanjang zaman dan untuk varian bangsa untuk dilihat secara
akal. Kekuatan al-Qur‟an mampu melemahkan semua ego manusia. Jelas
sekali di dalam komentarnya ini, bahwa beliau ini sangat kontekstual
dalam memposisikan suatu permasalahan, walaupun masalah tersebut
mempunyai nilai-nilai yang lebih dan membuat takjub.23
Adapun dari Sistematika penulisan tersebut merupakan kesimpulan
penulis yang berbentuk sementara. Penulis perlu untuk membaca tafsir
tersebut dari seluruhnya. Sehingga kemungkinan lain untuk dapat
mengkritisi dan mengubahnya atau mungkin menambahkan sesuatu yang
perlu ditambah.
2. Karakter Khas Tafsir al-Azhar
Pada setiap pemahaman tentang satu topik. Jelas Hamka secara
konsisten menutupnya dengan pesan etis yang disingkirkan dalam
23
Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1982), 12.
59
pembiaran. Dalam setiap pertunjukan dalam setiap pemahaman melalui
metodologi sosial daerah setempat, yang menunjukkan sejauh tradisi
melayu. Yayasan leluhurnya sebagai tokoh Melayu yang obsesif.
Kecenderungan untuk membuat masyarakat Melayu Islam sangat kental.
Apalagi bentuk penafsiran ini dalam bahasa Indonesia yang
mengutamakan tujuan penulisan untuk konsumsi pembaca dari komunitas
Melayu. Misalnya, ketika dia menafsirkan firman Tuhan dan Allah
menurut Hamka dalam bahasa Melayu firman Tuhan adalah Tuhan dan
Tuhan. Seperti yang diucapkan di batu Trengganu (disimpan di Museum
Kuala Lumpur) yang tercatat pada tahun 1303 M. Dalam firman Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā yang dapat dimaknai dengan maha mulia . Akhirnya
seiring dengan masa, kata Tuhan dipahami oleh orang Islam Indonesia
dan Melayu (T besar) diartikan dengan Allah. Sedangkan term dewa tidak
dipakai lagi. Beliau membandingkannya dengan term-term untuk Tuhan
dari bahasa lainnya, yaitu Gusti (Jawa), Pangeran (Sunda), Perang (Bugis
dan Makassar),24
susunan kata berirama puitis.
Salah satu sumber juga berasal dari buku-buku karya Cendekiawan
modern dan Orientalis Barat. Dia tidak malu untuk mengutipnya dari
buku-buku komentar Indonesia yang ditinggali orang-orang sezamannya.
Di antara komentar-komentar di Indonesia adalah Tafsir al-Furqān (A.
Hassan), Tafsir al-Qur'an al-Karim (Mahmud Yunus), Tafsir al-Nūr (M.
Hasbi al-Shiddiqi), Tafsir al-Qur'an al-Karim (Qasim Bakri), Depag Tafsir
dan lainnya.25
Keunikan bentuk penafsiran ini adalah kemampuannya untuk
berhubungan dengan isu-isu kontemporer, dengan budaya masyarakat,
24
Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 90. 25
Hamka, Tafsir al-Azhar 421.
60
khususnya budaya Melayu-Minangkabau, termasuk pengalaman hidupnya.
Misalnya, ketika ia menafsirkan surat al-Baqarah: 195. Itu berkaitan
dengan fi sabilillah. Ia bercerita tentang TNI yang dipimpin jenderal
Sudirman dan Front Hizbullah saat melawan Jihad fi Sabilillah. Dalam
menafsirkan surah al- Baqarah ayat 209 pada beberapa juz, Allah tidak
menyaksikan untuk mengikuti langkah setan, Hamka menceritakan
bagaimana negara atau individu Muslim menolak perintah Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā dan mengajak untuk mematuhi keputusan Kamal
Ataturk, pemimpin sekuler Turki. Ia juga menceritakan bagaimana
masyarakat Buton, Sulawesi mematuhi perintah Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā dan menerapkan hukum hudud bagi pencuri dan pezina. Meskipun
bekas koloni Belanda.. Beliau bahkan menceritakan pengalaman
pribadinya ketika berdiskusi dengan anaknya, menjelaskan beberapa ayat
seperti surah al-Baqarah: 219 yang berkaitan dengan tertutupnya
pertolongan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Terkait dengan apa yang di
sampai pada saat dipenjara. Beliau juga menceritakan pengalaman
gurunya dalam hal berpoligami ketika sedang menafsirkan Surah al-Nisa.
Pada saat penulisan tafsir yang diselesaikan ketika Hamka sedang
berada di dalam penjara. Sel penjara menurut Hamka untuk mujahadah
kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Beliau menggoreskan pena untuk
tafsir ini di penjara Sukabumi, sekitar di Bungalow “Herlina dan arjuna”
di Puncak. Atau di Mess Brimob di Mega Bandung, atau sedang berbuat
ketika ditahan di rumah sakit Persahabatan di Rawamangun.
Pada saat menulis komentar yang selesai saat Hamka berada di
penjara. Sel penjara menurut Hamka harus bermusuhan dengan Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā. Dia goreskan pulpen untuk penafsirannya ini di
lapas Sukabumi, sekitar bungalow "Herlina dan arjuna" di Puncak. Atau di
61
Mess Brimob di Mega Bandung, atau sedang dilakukan saat ditahan di
rumah sakit Persahabatan di Rawamangun. Pandangan jamaah kala itu
beliaulah yang terbayang ketika Hamka memulai menggoreskan penanya
untuk menulis sebuah tafsir.26
ia menulis komentar biasanya di pagi hari
saat fajar. Tulisan dimulai dari akhir 1958 hingga Januari 1964, dikatakan
bahwa panggung belum selesai. Agar catatan asli editor dipertahankan
keasliannya kemudian Hamka menulisnya di majalah Gema Islam dari
Januari 1962 hingga Januari 1964, tetapi yang dapat dimuat hanya satu
setengah juz, yaitu juz 18-19.
26
Hamka, Tafsir al-Azhar, 42.
63
BAB IV
ANALISIS KATA KETELADANAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR
Dalam bab IV ini, penulis akan memaparkan tentang pemahaman
maksud keteladanan menurut Buya Hamka. Sebelumnya memasarkannya
peneliti akan menjadikan 2 bagian maksud teladan, yang terdapat pada kitab
tafsir al-Azhar terdapat 3 ayat ,dan dua surah. peneliti dari masing -masing
keduanya berbeda pertama yang ditafsirkan Hamka pada surah al-Aḥzāb ayat
21 yang mengenai sikap teladan Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm ketika menghadapi peperangan melawan musuh-musuh Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā di perang Khandak. Dan yang kedua pada kitab tafsir
al- Azhar peneliti menemukan penjelasan isi maksud surah al-Mumtaḥanah
ayat 4 dan 6 itu mengenai sikap teladan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
memintakan ampunan kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā untuk ayah
A. Sikap Teladan Nabi Muhammad
Di dalam surah al-Aḥzāb ayat 21 menerangkan keteladanan Rasulullah
ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm sebagai berikut
ى لىقىد كىافى لىكيم ف ى كىاليػىوـى الهخرى كىذىكىرى الله رىسيوؿ الله ايسوىةه حىسىنىةه لمىن كىافى يػىرجيوا اللهثيػرنا كى
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia
banyak menyebut Allah." (Qs. al-Aḥzāb/ 33: 21)1
Suatu hal riwayat dari seorang istri Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm yang ikut menyaksikan melihat dari sebagian peperangan yang
1 Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009).420.
64
dialami Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm melaporkan tentang
kehebatannya kondisi di kalangan Muslimin pada saat peperangan Khandaq
itu. beliau mengatakan:“ aku telah menyaksikan di samping Rasulullah ṣɑllā
Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm beberapa peperangan yang kuat dan mengerikan,
peperangan di Al-Muraisi Khaibar dan kami pun telah menyaksikan
pertemuan dengan musuh di Hudaibiyah, dan saya pun turut ketika
menaklukan makkah dan peperangan di Hunain. Tidak ada pada semua
peperangan yang saya turut menyaksikan itu yang lebih membuat lelah
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm dan lebih membuat kami-kami jadi
takut, melebihi peperangan Khandaq, karena kaum muslimin benar-benar
terdesak dan terkepung pada waktu itu, sedang Bani Qurais (Yahudi) tidak
lagi percaya karena sudah berkhianat, sampai Madinah dikawal sejak siang
sampai waktu subuh, sampai kami dengar takbir kaum muslimin untuk
melawan rasa takut mereka, yang membebaskan kami dari bahaya yakni
sebab musuh-musuh sudah diusir sendiri oleh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā
dari tempatnya mengepung itu dengan rasa jengkel serta sakit hati, sebab
itikad mereka tidak tercapai.” Itulah suatu riwayat ummi Salamah.
Akan tetapi di saat-saat yang sangat mengagetkan hati itu, ada suatu
contoh teladan yang patut ditiru, tidak terdapat lain melainkan Rasulullah
ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm sendiri. Pasti benar apa yang dikatakan oleh
surah al-Aḥzāb ayat 21 dalam al-Qur‟an, yang maksudnya” sebetulnya
merupakan untuk kalian pada Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm itu
teladan yang baik.” Memanglah terdapat orang-orang yang berguncang
pikirannya, berpenyakit jiwa, pengecut, munafik, tidak berani tanggung
jawab, siapa hendak lari jadi suku baduy kembali ke dusun-dusun, tenggelam
dalam ketakutan memandang dari jauh betapa besarnya jumlah musuh yang
hendak menyerbu, namun masih terdapat lagi orang-orang yang memiliki
pendirian senantiasa, yang tidak putus harapan, kehabisan akal, karena
65
mereka memandang sikap dan tingkah laku pemimpin besar mereka sendiri,
ialah Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm.2
Tentulah banyak hal yang bisa menginspirasi diri, dari seorang
Rasulullah ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm karena memiliki akhlak yang baik,
dengan demikian setiap tindakan dan ucapannya selalu ditiru dan dijadikan
pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun juga beliau tidak
pernah menodai kepercayaan dari orang sekelilingnya, adapun kata akhlak
berasal dari watak, tabiat, keberanian, dan agama. Namun menurut Ibnu
Miskawaih akhlak secara istilah adalah sebagai berikut. “Suatu keadaan bagi
jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa
melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal
dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-
ulang. Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan
pertimbangan, kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat
dan akhlak.”
Suatu akhlak yang diajarkan oleh gurunya akan menjadi keteladanan
dan akan menjadi pembiasaan terhadap diri siswa yang baik. Indikasi bahwa
akhlak dapat dipelajari dengan metode pembiasaan, meskipun pada awalnya
anak didik menolak atau terpaksa melakukan suatu perbuatan atau akhlak
yang baik, dengan seiringnya waktu berjalan setelah lama dipraktekkan
secara terus-menerus akhirnya anak tersebut menjadi kebiasaan yang baik.
Adapun menurut al-Ghazali di dalam kitabnya Iḥya ‟Ulūmuddin yang dikutip
oleh Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari tentang definisi akhlak sebagai
berikut.
2 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1992), 223.
66
”suatu ungkapan tentang keadaan pada jiwa bagian dalam yang melahirkan
macam-macam tindakan dengan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan
pertimbangan terlebih dahulu3”
Keteladanan ini dianggap penting, karena aspek agama yang terpenting
adalah akhlak yang terwujud dalam tingkah laku. Untuk mempertegas
keteladanan Rasulullah, al-Qur‟an lebih lanjut menjelaskan akhlak Nabi
yang tersebar dalam berbagai ayat di dalam al-Qur‟an. Misalnya, dalam surat
al-Fath disebutkan bahwa sifat Nabi beserta pengikutnya itu bersikap keras
terhadap orang-orang kafir akan tetapi berkasih sayang pada mereka,
senantiasa ruku‟ dan sujud (salat), mencari keridhaan Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā. Pada ayat lain dijelaskan bahwa diantara tugas yang dilakukan Nabi
adalah menjadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru
kepada agama 4Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang
meneranginya.
1. Sumber Akhlak
Dalam sebuah ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu bermula
pada masa saat Agama Islam, karena sebab melindungi martabat manusia
agar tidak mengalami hal penurunan tentunya yang akan berdampak dengan
membandingkan suatu martabat dengan hewan. Kesetaraan pada akhlak
menurut Islam sangatlah berarti, sebab akhlak ialah sesuatu buah dari tauhid
yang tertanam dalam jiwa manusia, agar supaya menjadikan manusia yang
baik serta berbudi luhur.
3 Muhammad Rabbi Jauhari, Akhlaqunai, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 88.
4 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 95.
67
a. Firman Allah (al-Qur‟an) dan sunnah (hadis)
Suatu hal mengenai agama Islam terdapat sebuah landasan normatif
seperti halnya itu akhlak pada manusia yang dapat dicontohkan nabi dan
rasul dengan syariat yang terkandung dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah.
Adapun dalam firman Allah sebagai berikut.
كىانكى لىعىلهى خيليقو عىظيمو “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti
yang luhur.” (Qs. al-Qalam/ 68: 4)5
Hamka mengatakan inilah satu pujian yang paling tinggi yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang jarang diberikan kepada Rasul yang
lain.6 Ayat di atas menyatakan bahwa Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih
wɑ sallɑm. memiliki akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu, seluruh umat
manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm. wajib menjadikan akhlak beliau sebagai rujukan perilaku dan suri
teladan.7
b. Ke-Esaan Allah (Tauhid)
Kata tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu waḥadda, yūwaḥidu,
taūhid, artinya adalah mengesakan Tuhan. Tauhid secara bahasa ialah
meyakini keesaan Allah atau meyakini bahwa dia hanya satu, tunggal tidak
ada sekutu baginya. Menurut istilah bahwa di dunia ini hanya ada satu
Tuhan, yaitu Allah Rabb al-„Alamiin.8
Karena bertauhid itulah yang dapat menyebabkan terpandangnya suatu
harga diri serta merelakan mati agar memperjuangkannya. Sebab dalam
5 Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 564.
6 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 29 (Jakarta: Pustaka PanjiMas, 1983) 37.
7 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 51.
8 Bakri Dusar, Tauhid dan Ilmu Kalam, (Padang: IAIN –IB Press, 2001), 21.
68
ajaran tauhid itulah pada dasarnya hakikat mati tidaklah begitu besar lagi,
Yang Maha Besar itulah menuntut ridanya Allah Subḥānahu wa ta‟ālā oleh
karena itu yang dapat dinamai dengan suatu i‟tikad atau kepercayaan. Pokok
pertama dari pendirian itulah suatu hakikat yang membentuk budi dalam
ajaran Nabi serta junjungan kita Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm .9
Dengan mendasar suatu kepercayaan tauhid yang ditanamkan melalui
sebuah Agama yang mana diajarkan oleh Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm adalah membentuk suatu akhlak yang tabah dan teguh.
Karena dengan Akhlak yang teguh itulah dapat dikuatkan lagi oleh suatu
pokok kepercayaan, yaitu takdir, segala sesuatu di dalamnya itu. Sejak dari
kejadian langit dan bumi, sampai kepada makhluk yang sekecil–kecilnya,
adanya dengan ketentuan serta jangka waktu. Sebab hidup pun menurut
jangka waktu, mati pun menurut ajal.10
Adapun Buya Hamka menurutnya dengan tauhid inilah sebagai bentuk
sumber dalam suatu kehidupan bagi orang-orang muslim, tentu halnya
sebagai sumber suatu akhlak. Sebab beliau berkata bahwa “percaya kepada
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā adalah suatu bentuk yang mana dapat
menghilangkan rasa takut dan ragu” setelah itu beliau memperkuat dengan
pernyataan sebagai berikut.
Dengan tauhid itulah yang menyebabkan timbulnya rasa keyakinan dan
siap bersedia mati untuk memperjuangkan Islam. Karena ajaran tauhid itu
hakikat mati tidaklah begitu besar lagi, karena sebab yang maha besar adalah
menuntut keridhaan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā, jadi itulah yang dinamai
Itikad atas dasar kepercayaan. Suatu pokok dari pendirian itulah dengan
9 Hamka, Lembaga Budi, (Jakarta: pustaka Panjimas, 1963) , 53.
10 Hamka, Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial Budaya, Politik (Jakarta:
Pustaka Panjimas, 2002), 13.
69
hakikat yang akan membentuk budi luhur dalam suatu pengajaran oleh Nabi
Muhammad ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ sallɑm.11
Bertauhid dan berakhlak suatu hal dapat memiliki hubungan erat,
karena tauhid menyangkut aqidah serta keimanan, sedangkan akhlak yang
baik menurut pandangan Islam, Haruslah berpijak pada suatu keimanan.
Sebab iman tidak cukup sekedar disimpan di dalam hati, tetapi harus
dilahirkan dalam perbuatan nyata dan dalam bentuk amal saleh. Sedangkan
jika keimanan melahirkan amal saleh, barulah dikatakan iman itu sempurna
karena telah direalisasikan. Jelas bahwa Ahklak karimah merupakan mata
rantai dari keimanan.
Hal yang perlu dipahami dari suatu sumber akhlak ialah suatu tindakan
akhlak bagi seorang muslim tentunya perlunya kepercayaan kepada Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā yang Maha Esa. Oleh sebab itu Buya Hamka
berpendapat bahwa dengan bertauhidlah yang dapat menggerakkan segala
sesuatu aktivitas yang dilakukan pada seorang muslim. Karena tanpa suatu
itikad tauhid maka tindakan dalam sebuah perbuatan tersebut tidak ada nilai
dalam pandangan Islam.12
c. Berpikir (Akal)
Tentu halnya Buya Hamka menurutnya akal adalah sebuah anugerah
dari Allah Subḥānahu wa ta‟ālā yang berikan kepada makhluk pilihannya itu
manusia.13
Karena Anugerah yang diberikan terhadap makhluknya seperti
Akal yang dapat memiliki suatu hubungan dasar membedakan antara
manusia dengan makhluk yang lainnya dalam hal suatu perbuatan. Dengan
akal manusia dapat melakukan perenungan apa yang diperbuatnya.
11
Hamka, Lembaga Budi, 55. 12
Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 66. 13
Hamka, Pelajaran Agama Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 185.
70
Suatu paparan di atas oleh Hamka menunjukan bahwa anugerah yang
diberikan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā berupa akal, tentu halnya dengan akal
yang mana mempunyai hubungan dengan akhlak. Adapun dengan akal
memiliki kebebasan untuk mencari suatu hal dengan sebatas wilayah yang
dapat dijangkaunya. Buya Hamka menurutnya itu dengan akal itulah
manusia dapat mempunyai kecerdasan, karena kemampuan tersebut dapat
memberikan untuk menilai dan mempertimbangkan perbuatan manusia yang
dilakukan sehari-hari.14
Tentu halnya demikian Buya Hamka memposisikan akal padahal yang
sangat berarti pada diri manusia, karena dengan adanya akal pada manusia
dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan yang jelek. Perbedaan dengan
makhluk lainnya, akal mempunyai kecerdasan yang dapat menjadikan nilai
dan pertimbangan manusia dalam menjalani suatu kehidupannya.
B. Sikap Teladan Nabi Ibrāhīm
Sedangkan di dalam surah al-Mumtahanah ayat: 4 dan 6 keteladanan
Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām. sebagai berikut:
مىعىو كىالذينى ابػرهىيمى قىد كىانىت لىكيم ايسوىةه حىسىنىةه ف ؤيا ا لقىومهم قىاليوا اذ ن بػيرىءه
ا بكيم كىفىرنى منكيم كىما تػىعبيديكفى من ديكف الله نػىنىا كىبىدى نىكيمي بػىيػ اكىةي كىبػىيػ ءي العىدى كىالبػىغضىا
ا كىحدىه بلله تػيؤمنػيوا حىته اىبىدن ىستػىغفرىف لىبيو ابػرهىيمى قػىوؿى ال لىكى اىملكي مىاكى لىكى لىنىا كىالىيكى تػىوىكلنىا عىلىيكى رىبػنىا شىيءو من الله منى صيػري كىالىيكى اىنػىبػ المى
“Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrāhīm
Alaīhi al-salām dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika
mereka berkata kepada kaumnya,“Sesungguhnya kami berlepas diri
dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami
mengingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu
ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu
14
Hamka, Pelajaran Agama Islam, 184.
71
beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrāhīm Alaīhi al-
salām kepada ayahnya, ”Sungguh, aku akan memohonkan ampunan
bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah
terhadapmu.” (Ibrāhīm Alaīhi al-salām berkata), “Ya Tuhan kami,
hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau
kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali,”(Qs.al-
Mumtaḥanah / 60: 4)15
ى كىاليػىوـى الهخرى ايسوىةه لىقىد كىافى لىكيم فيهم نىةه لمىن كىافى يػىرجيوا الله فىاف يػتػىوىؿ كىمىن حىسىى دي احلىمي الغىن ىيوى الله
“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrāhīm Alaīhi al-salām dan
umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang
mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian.
Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah
yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. al-Mumtaḥanah/ 60: 6)16
Suatu ayat di atas sebuah gambaran seseorang yang menjadikan contoh
teladan dalam hal kehidupan sehari-hari yaitu Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
suatu hal perbuatan baik kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak
untuk mendoakannya, dalam hal ini orang tua tersebut berbeda keimanan
tetapi selagi di dunia atau masih hidup perlu mendoakannya dan selagi tidak
memusuhi kita dalam Agama atau menjadi musuh Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā yang nyata. Sebagaimana yang Allah perintahkan untuk meneladani
perbuatan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām kecuali perbuatannya yaitu ketika
mendoakan orang tuanya yang jelas menjadi musuh Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā.
15
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 913. 16
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 913.
72
1. Berbuat baik kepada orang tua
ى رىب كى اىل تػىعبيديك هي ال ا كىقىضه ين اي ننا كىبلوىالدى ليغىن اما احسه اىك اىحىديهيىا الكبػىرى عندىؾى يػىبػا ا تػىقيل فىلى كلههيمى ا كىقيل تػىنػهىرهيىا كلى ايؼو ليمى ا كىاخفض كىرينا قػىولن ليمى نىاحى لىيمى منى الذ ؿ جى
رناالرحى ا رىبػيهن غىغيػ ة كىقيل رب ارحىهيمىا كىمى
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau
membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan
yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh
kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu
kecil.”(Qs. al-Isrā/ 17: 23-24)17
يو حيسننا نسىافى بوىالدى نىا ال ؾى كىاف كىكىغيػ فىلى علمه بو لىكى لىيسى مىا ب لتيشرؾى جىاىىدهتيم بىا فىاينػىبئيكيم مىرجعيكيم الى تيطعهيمىا تػىعمىليوفى كينػ
“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada
kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai
ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya
kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa
yang telah kamu kerjakan.” ( Qs. al-„Ankabūt/ 29: 8)18
Hal yang terdapat pada ayat di atas menunjukan suatu yang biasa
dilakukan kepada orang tua. Tidak semestinya orang yang lebih besar suatu
jasanya melainkan kepada orang tua. Karena keduanya telah mengalami
suatu kesulitan dalam menjaga dan merawat. Ialah seorang ibu yang telah
17
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 417. 18
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 619.
73
menderita kepayahan serta kelemahan berbulan-bulan lamanya di saat masih
di dalam rahimnya, sebab berbaktilah kepada orang tua adalah suatu yang
patut dikerjakan bahwa beliau adalah di antara amal salih yang dapat
melapangkan suatu kesulitan dan menghilangkan keredupan.
Karena menghargai orang tua suatu berbakti dan berbuat baik kepada
mereka, menyayanginya sebagaimana mereka merawat dari semenjak kecil,
serta tidak menyakiti dengan suatu perasan mereka, membantunya dalam
kesusahan pada mereka dan berbicara kata dengan penuh kelembutan serta
selalu mendoakan mereka.
Dengan kedua orang tua itu adalah suatu hal pedoman dalam
kehidupan merekalah dengan bisa hidup sampai sekarang. Tanpa melalui
pengorbanannya dapat merasakan suatu pendidikan yang lebih baik, dengan
melalui doa merekalah bisa mencapai cita-cita kita dan mampu mencapai
kesuksesan. Karena sebab orang tua hanya minta satu hal dari anaknya untuk
melihat anaknya sukses atas pengorbanan dan pendidikan yang tiada
terhingga. Maka dari itu jadikanlah orang tuamu sebagai guru terbaik dalam
sejarah kehidupanmu.19
Suatu hal dari sebuah kebaikan, dalam agama Islam memberikan suatu
prinsip-prinsip akhlak yang perlu dilakukan oleh anak kepada orang tuanya
antara lain sebagai berikut:
1. Mentaati suatu tindakan orang tua, tentu hal namun hal maksiat.
2. Berbuat baik dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih kepada
orang tua.
3. Berkatalah dengan sopan santun kepada orang tua.
4. Merendah diri ketika orang tua marah.
19
Candra Himawan & Neti Suriana, Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah
(Yogyakarta: Pustaka Al-bana, 2013), 117.
74
5. Berterima kasih kepada orang tua yang telah merawatnya dari
bayi sampai dewasa.
6. Bermuka ceria ketika berpapasan dengan keduanya.
7. Mencium tangan saat hendak pulang maupun pergi.
8. Memperbanyak berdoa dan meminta ampunan untuk keduanya.
9. Setelah wafat: salatkan jenazahnya, memohonkan ampun,
menyempurnakan janjinya, menghormati sahabatnya dan
meneruskan jalinan kekeluargaan yang pernah dibina oleh
keduanya.
2. Bertawakal.
ت كىالىرض كىالىيو يػيرجىعي الىمري كيل و وه لله غىيبي السمه رىب كى كىمىا عىلىيو كىتػىوىكل فىاعبيدهي كى تػىعمىليوفى عىما بغىافلو
Artinya:”Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepada-Nya
segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-
Nya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu
kerjakan”.(Qs. Hūd/ 11: 123)20
كىتػىوىكل عىلىى احلىي الذم لى يىيوتي كىسىبح بىمده ى عبىاده بذينػيوب بو كىكىفهبيػرنا خى
“Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup, Yang tidak mati, dan
bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa
hamba-hamba-Nya,”(Qs. al-Furqān/ 25: 58) 21
Pada ayat di atas tersebut bahwa orang yang bertawakal kepada Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā akan mengerjakan suatu usaha, bahwasannya tentu
hasilnya akan merasakan sesuatu yang telah membuat ketentuan dari Allah
20
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 338. 21
Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid: 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2009). 563.
75
Subḥānahu wa ta‟ālā. Oleh sebab itu terjadilah yang tidak diinginkan, sebab
dia juga pun yakin bahwa setiap perlakuan yang menimpa dirinya baik
ataupun buruk serta musibah dan nikmat semuanya itu memperoleh suatu
hikmah terhadap kebaikan teruntuk bagi dirinya.
Adapun tawakal adalah langkah dari serangkai rentetan usaha yang
dilakukan oleh seorang mukmin dalam bekerja untuk dunia maupun akhirat
nya. Tawakal suatu kondisi hati di saat mengharapkan hasil terbaik dari
segala apa yang diusahakannya, dan sekaligus kesiapannya untuk menerima
hasil yang terburuknya. Tawakal juga merupakan sikap mental seorang yang
di hatinya penuh dengan sinar keimanan dan keyakinan. Sikap mental juga
yang mendasari keyakinan di kalangan para sufi, sebab tawakal merupakan
hasil dari keyakinan yang pasti kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Sikap
tawakal akan berubah ke bahagian dan ketentraman hati. Ketika hati tenang,
pikiran pun terasa jernih untuk berpikir dalam hal mencari solusi serta
menghadapi masalah yang sedang dihadapi.22
3. Bertaubat
ا تػىوبىةن الله الى ا تػيوبػيو اهمىنػيوا الذينى اىيػ هىا مه ى نصيوحن كيم عىن ي كىفرى اىف رىب كيم عىسهري ا الىنػهه ياهتكيم كىييدخلىكيم جىنهتو تىرم من تىتهى ي ييزل لى يػىوـى سى اهمىنػيوا كىالذينى النب الله
مىعىو اغفر لىنىاكى نػيورىنى لىنىا اىتم رىبػنىا يػىقيوليوفى كىبىيىانم اىيديهم بػىيى يىسعهى نػيوريىيم قىديػره شىيءو كيل عىلهى انكى
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan
taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan
menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika
Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman
22
Supriyanto, Tawakal Bukan Pasrah (Jakarta: Qultum Media, 2010), 8.
76
bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan
di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata,“Ya Tuhan kami,
sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami;
Sungguh, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. al-Tahrīm/
66:8)23
Ayat di atas menunjukan bahwa Allah Subḥānahu wa ta‟ālā
memerintahkan kepada seluruh kaum mukmin bertobat kepadanya, walaupun
kita taat dalam beribadah.
Adapun taubat adalah meninggalkan suatu perbuatan dosa karena
mengetahui kehinaannya, menyesal sebab pernah melakukan, dan
berkeinginan keras dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Di samping
itu, dengan amalan yang kemungkinan dikerjakan dari berbagai amalan yang
dulu diabaikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pernah
ditinggalkan karena ikhlas kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Hanya
mengharapkan pahalanya, dan takut akan siksa yang telah diperbuatnya kala
itu. karena taubat itulah syarat nyawa belum sampai di tenggorokan dan
matahari belum terbit dari arah terbenamnya (barat), maka seseorang
menyadari akan kesalahannya dan menyesali apa yang diperbuatnya di kala
itu, dengan niat yang baik hendak mengubah tingkah lakunya untuk masa
yang akan datang. Serta mohon ampunlah kepada Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Niscaya Allah Subḥānahu
wa ta‟ālā akan mengampuni dosa sebab kesalahan yang diperbuatnya.
Karena Allah Subḥānahu wa ta‟ālā, itu Maha Pengampun, Maha Pemurah,
Maha Penyayang.24
23
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen
Agama, 2009), 543. 24
Muhammad bin Ibrahim al-Hamid, Cara Bertaubat Menurut Al-Qur‟an dan As-
Sunnah, Terj. Muhiburrahman (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2007), 138.
77
4. Berdoa
قىريبه فىان بػيوا دىعىاف اذىا الداع دىعوىةى ايجيبي كىاذىا سىاىلىكى عبىادم عىن ل فػىليىستىجيػ ا ب لىعىلهيم يػىرشيديكفى كىليػيؤمنػيو
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang
Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang
berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka itu memenuhi
(perintah) Ku dan beriman kepadaKu, agar mereka memperoleh
kebenaran.”(Qs. al-Baqarah/ 2: 186)25
ب لى انو ايدعيوا رىبكيم تىضىر عنا كخيفيىةن الميعتىدينى يي
“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut.
Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(Qs. al-
A„rāf/ 7:55)26
Doa dalam istilah agama adalah permohonan hamba kepada Tuhan
agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan, baik buat si
pemohon maupun pihak lain. Permohonan tersebut harus lahir dari lubuk hati
yang terdalam disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepada-Nya.
Pada al-Qur‟an terdapat sebuah perintah melakukan shalat dan doa disertai
dengan ketabahan sebagai sarana untuk meraih suatu kebutuhan. Hal ini
dapat dipahami setiap doa tanpa ketabahan dalam usaha, belum menjadikan
suatu jaminan terpenuhi harapannya. Karena Janji Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā yang menyatakan bahwasannya “Aku perkenankan doa yang akan
dimohon maka bermohonlah kepadaku”.
Dalam hal ini doa adalah sebuah pengakuan akan lemahnya diri ini di
hadapan kuasa Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Sedangkan manusia hanya
memiliki usaha. Tetapi segala usaha yang kita kerjakan semua itu berada
pada hak kuasa Allah Subḥānahu wa ta‟ālā yang Maha Kuasa. Karena usaha
25
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 41. 26
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 224.
78
itu wajib untuk dilakukan, tapi hasilnya itu ketentuan Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā. Sebab usaha kita harus di iringi dengan doa walaupun sekeras apa
usaha kita kalau Allah Subḥānahu wa ta‟ālā tidak mengizinkan apa yang
inginkan tidak akan terwujud.27
Adapun penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa doa itu sebuah
pengakuan seorang hamba kepada Tuhanya, karena hamba tersebut makhluk
yang lemah tidak berdaya dan selalu membutuhkan akan pertolongan Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā.
Pada ayat 4 surah Mumtaḥanah maksudnya ialah wahai orang-orang
beriman, sudah ada suri teladan buat kalian pada Ibrāhīm Alaīhi al-salām
kekasih al-Rahman. Suatu kehidupan nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām bisa
kalian jadikan contoh, begitu pula orang-orang beriman yang ada
bersamanya kalangan nabi dan Allah.28 Sudah ada bagimu teladan yang baik
(untuk diikuti) pada Ibrāhīm Alaīhi al-salām. dan orang yang bersama dia
yaitu Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām sangat lemah lembut hati yang patuh
kepada ayah dan masyarakatnya. Beliau mengingatkan kepada mereka dari
penyembahan berhala dan perbuatan dosa. Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
berdoa untuk ayahnya, tapi tatkala ayahnya dan kaumnya itu menjadikan
musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
melepaskan diri dari mereka dan meninggalkan kampung halamanya serta
meninggalkan ayahnya, kaum, negerinya.29 Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
dan orang-orang yang telah menyertakan beliau dalam keadaan beriman,
27
Abu Ezza, Setiap doa Pasti Allah kabulkan: Doa dahsyat menjadikan orang hebat,
cet I (Jakarta: Qultum Media), 56. 28
Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari,, Tafsir al-Thabari, Tejr. Fahturrozi
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 934. 29
Abdullah Yusuf Ali, Tafsir Yusuf Ali teks, terjemah dan Tafsir al Qur‟an 30 Juz,
Cet 3 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 1455.
79
yang telah mempersiapkan diri dengan tidak ragu-ragu menuruti langkah
beliau.30
Dalam ayat ke 4 pada surah al-Mumtaḥanah ini ditunjukan kepada
keteladanan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām untuk dijadikan contoh, dalam
perjuangan beliau untuk menegakan agama Allah Subḥānahu wa ta‟ālā tidak
pula kurang hambatan, rintangan dan halaman yang beliau temui dengan
kaumnya, namun segala gangguan itu tidaklah membuat beliau bekisar dan
beranjak dari pendirian yang kuat.
Adapun sebagian dari orang-orang mukmin mendoakan dan
memohonkan ampunan untuk bapaknya mereka lalu mengatakan Nabi
Ibrāhīm Alaīhi al-salām memohonkan ampun untuk bapaknya. Allah
Subḥānahu wa ta‟ālā berfirman:
ا يستػىغفريكا للميشركيى كىلىو كىانيو اىف ا للنب كىالذينى اهمىنػيو مىا كىافى من قػيربه ايكل ى مىا بػىعد بي اىنػهيم لىيم تػىبػىي عىن ال لىبيو ابػرهىيمى استغفىاري كىافى كىمىا الىحيم اىغحه
ةو ا موعدى هي كعىدىىى ى فػىلىما اي لىو تػىبػىي ىكاهه ابػرهىيمى اف منوي تػىبػىراى لله عىديك واىن لىليمه حى
“Tidak pantas bagi Nabi dan Orang-orang yang beriman memohonkan
ampunan ( kepada Allah) bagi orang-orang musyrikin, sekalipun orang-orang
itu kaum kerabatnya, setelah jelas, bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik
itu penghuni neraka jahanam. Adapun permohonan ampunan Ibrāhīm Alaīhi
al-salām (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak hanya lain hanyalah karena
suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya, maka Nabi Ibrāhīm
Alaīhi al-salām berlepas diri darinya. Sungguh Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
itu seorang yang lemah lembut hatinya lagi penyantun”. (Qs. al-Taubah/ 9:
113-114)31
Jadi ayat di atas tadi menjelaskan janganlah kamu berbasa-basi dengan
mereka dan jangan pula kamu tampakkan kepada mere rasa kasih, serta
30
Hamka, Tafsir Al-Azhar, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000), 97. 31
Kementerian Agama R.I, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 296.
80
jangan kamu memohonkan ampunan untuk mereka sebagaimana dilakukan
Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām terhadap ayahnya, karena Nabi Ibrāhīm Alaīhi
al-salām itu memohonkan ampunan untuk ayahnya sebelum dia mengetahui
bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā. Tetapi setelah
ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, maka jelaslah bagi Nabi Ibrāhīm
Alaīhi al-salām keadaan itu. lalu dia pun meninggalkan permohonan
ampunan untuk ayahnya. Sedangkan bagimu permusuhan ayahmu telah jelas,
karena mereka kafir kepada rasul dan mengusir kamu dari kampung
halaman. Oleh karena itu tidaklah patut bagimu memohonkan ampun untuk
mereka.32
Kecuali perkataan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām terhadap ayahnya,
maksudnya agar tidak usah meniru dan meneladani apa yang diucapkan Nabi
Ibrāhīm Alaīhi al-salām kepada ayahnya: Sungguh aku benar-benar hendak
memohonkan ampunan untuk ayah tetapi aku tidak berkuasa apa-apa untuk
ayah dari Allah Subḥānahu wa ta‟ālā sedikit juga pun. Karena sikap Nabi
Ibrāhīm Alaīhi al-salām memohonkan ampun untuk ayahnya tercinta, tetapi
“musuh Allah” itu, hendaklah dikecualikan, janganlah diikuti tetapi beliau
berlepas diri dari ayahnya setelah nyata bahwa dia musuh Allah. Sebab itu
dapatlah dipahami dari ayat ini bahwa tidak boleh berdo‟a kepada orang
kafir diberi ampunan terutama yang sudah meninggal, melainkan serahkan
sajalah hal-ihwalnya itu kepada kebijaksanaan tuntunan Allah Subḥānahu wa
ta‟ālā. Maksud yang utama dengan sikap ini adalah untuk memperteguh
keyakinan dan „aqidah, jangan sampai kacau balau.
Maksudnya ayat ke-6 dalam surah al-Mumtaḥanah Ayat ini
mengulangi perintah menjadikan Ibrāhīm as dan orang-orang yang beriman
besertanya sebagai suri teladan yang baik dengan maksud agar perintah itu
32
Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maragi, Juz 28 (Mesir: Maktabah Mustafa
al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1946), 107-108.
81
wajib diperhatikan orang-orang yang beriman. Sikap Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-
salām terhadap orang-orang kafir itu adalah sikap yang benar.33
Sungguh
pada mereka, yakni pada sikap mereka dalam berdoa dan bertawakal kepada
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā, dan menjauhkan diri dari perbuatan kejahatan.34
Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrāhīm Alaīhi al-salām dan umatnya) ada
teladan yang baik bagimu. Maksudnya, pada Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām
dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para nabi dan para wali, yakni
dalam hal membebaskan diri dari orang-orang kafir.35 Hal tersebut sudah
ada teladan yang baik bagimu dan barangsiapa yang mengharapkan dari
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan hari kemudian, tetapi barang siapa berpaling,
sungguh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā Maha kaya, Maha Terpuji. Yaitu: Jika
ada orang yang menolak peringatan dan undang-undang Allah, dia akan rugi
sendiri. Bukan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā yang memerlukan
penyembahannya atau puji-pujiannya. Allah Subḥānahu wa ta‟ālā bebas dari
segala kekurangan dan sifat-sifat-Nya memang sudah terpuji.36 Dan barang
siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Subḥānahu wa ta‟ālā Dialah yang
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya adalah siapa yang berpaling tidak
mau melaksanakan perintah Allah Subḥānahu wa ta‟ālā melalui kalian dan
orang lain. Dia tidak patuh karena kesombongan.37
Sesungguhnya adalah
bagi kamu pangkalan ayat 6 surah al-Mumtaḥanah Yaitu bagi kamu orang
yang beriman dan mengikuti langkah tujuan suri teladan dari Nabi
Muhammad Subḥānahu wa ta‟ālā. “Pada mereka itu suri teladan yaitu pada
Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām dan orang-orang yang beriman bersamanya itu,
33
Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Tafsirnya, (Yogyakarta:
Menara Kudus, 1990), 105. 34
Abdullah Yusuf Ali, Tafsir Yusuf Ali Teks, 1456. 35
Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi,18, Terj. Dudi Rosyadi, cet. 1 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009), 357. 36
Abdullah Yusuf Ali, Tafsir Yusuf Ali Teks, 1456. 37
Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Thabari, jami‟ al-bayan al-ta„wil al-Qur‟an,
Terj. Abdul Somad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 940-941.
82
bagi barangsiapa yang mengharapkan Allah Subḥānahu wa ta‟ālā dan hari
kemudian. Orang-orang yang beriman pastilah mempunyai harapan, harapan
utama ialah Rahmat dan Ridha Allah, keselamatan di dunia dan di akhirat.
Puncak cita ialah bertemu dengan Tuhan. Orang yang tidak ada iman,
tidaklah mempunyai harapan akan hari esok, atau hari akhirat. Hal ini
mengutip apa yang dikatakan Zakariya, kata uswah yang maksudnya itu bisa
dikatakan dengan mengikuti. Jadi kata mengikuti dapat disimpulkan bahwa
sikap teladan yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm. mempunyai kaitannya dengan Nabi Ibrāhīm „alīh al-salām
mengenai dalam hal ajaran menyebarkan kebaikan sepertinya halnya itu
berdakwah di jalan Agama Allah Subḥānahu wa ta‟ālā yaitu agama Islam
yang disampaikan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām menjadikannya contoh
kepada umatnya agar selalu beriman kepada Allah Subḥānahu wa ta‟ālā.
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam kitab tafsir al-
Azhar karya buya Hamka penulis menemukan, terdapat 3 ayat al-Qur‟an
mengenai keteladanan yakni: surah al-‟Aḥzāb ayat 21 dan surah al-
mumtaḥanah ayat 4 dan 6.
Contohnya ketika perangan Khandak Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm tetap teguh dalam pendirian pada situasi tersebut kaum
muslimin yang jumlahnya tidak banyak lalu kaum kafir yang jumlahnya
melebihi banyak dari kaum muslim. Ketika itu Nabi serta para sahabat dan
kaum muslimin melihat jumlah musuh lebih banyak hati para kaum
Muslimin mulai terombang ambing. pada situasi tersebut ada sebagian yang
bertahan dan sebagian melarikan diri dari peperangan yang jumlahnya lebih
banyak. Tapi hasilnya beda dengan sikap teladan Nabi yang selalu teguh
dalam pendiriannya menghadapi musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā.
Contoh kedua sikap keteladanan nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām dalam
menghadapi musuh Allah Subḥānahu wa ta‟ālā terhadap Ayahnya, Nabi
Ibrāhīm Alaīhi al-salām tetap selalu sabar untuk mendoakan ayah yang
masih tidak mau mengikuti ajaran agama Allah yaitu Islam. Dalam setiap
upaya usaha yang dilakukan Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām berserah diri
memohon ampun kepada Allah agar ayahnya tersebut dapat memeluk agama
Allah Subḥānahu wa ta‟ālā yaitu Islam, tetap saja ayah Nabi Ibrāhīm Alaīhi
al-salām tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya mati dalam
keadaan kafir.
84
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Keimanan dan ketakwaan harus ditingkatkan sebab dengan itulah
hal paling pokok agar mencerminkan seorang muslim yang telah
dicontohkan sikap teladan Nabi dan Rasul ṣɑllā Allᾱhu ‟alaih wɑ
sallɑm itulah yang diajarkan dalam al-Qur‟an dan hadits.
2. Sikap tegas dalam keluarga itu orang tua yang membimbing
anak-anak untuk menjadi baik identiknya dalam masalah ibadah
khususnya Shalat yang lima waktu, mengaji dalam bentuk cara
membaca al-Qur‟an. Karena orang tua sebagai guru pembina
sekaligus pengawas yang pertama kali mengajarkan ketika masih
kecil hingga kelak dewasa nanti.
Keteladanan sesuatu yang perlu dipelajari atau dipahami agar apa yang
dikerjakan dalam hal sehari - hari tidak salah (sesat) sesuai ketentuan dalam
al-Qur‟an dan Hadits . Contohnya seperti Nabi Muhammad ṣɑllā Allᾱhu
‟alaih wɑ sallɑm meneladani kepada peristiwa kejadian pada zamannya
Nabi Ibrāhīm Alaīhi al-salām dalam hal berkurban, berhaji, Umrah karena
perbuatan tersebut masih dilakukan oleh kaum muslim saat ini.
85
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Malik Karim. Di Bawah Lindungan Ka‟bah. Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 2001.
Ali, Fachri. “Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia: Catatan Pendahuluan
Riwayat dan Perjuangannya”. Prisma, vol 12, no 2, (Februari 1983):
375-408.
Amin, Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. Tafsir al-Azhar, jilid 9. Singapura:
Pustaka Nasional PTE ELTD, 1999.
Bakry, Oemar, Tafsir Rahmat, cet. III. Jakarta: Mutiara, 1984.
------- Tafsir Rahmat, cet. III. Jakarta: Mutiara, 1986.
Chamami, Rikza. Dalam Studi Islam Kontemporer Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2002.
Damami, Mohammad. Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka
Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Dzakiey, Hamdani Adz-Bakran. Prophetic Intelligence, Kecerdasan
Kenabian. Yogyakarta: Islamika, 2006.
Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter, cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2012.
Hamka. Lembaga Budi. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
-------. Tafsir al-Azhar, juz 1, 3, 5, 8. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.
-------. Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya. Jakarta: PT Pustaka
Panjimas, 2005.
-------. Kenang-kenangan Hidup, jilid 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
-------. Tasawuf Modern. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
Hamka, Rusydi. Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Jakarta Selatan:
Pustaka Mizan Publikasi, 1981.
86
Haris, Abd. Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional religius, cet. 1
Yogyakarta: Pustaka Lkis Printing Cermelang, 2010.
Hatta, Ahmad, Tafsir Qur‟an Perkata, cet. 3. terj. Jakarta: Maghfirah
Pustaka, 2011.
Jamal, Imām Sulaimān bin Umār al-Ajāyay asy-Syāfi‟ī Asy-Syahīr bil, al-
Futhūḥat al-„Ilhᾱyyah bi Taudiḥ Tafsīr Al- Jalᾱlaīn al-daqᾱ„iq al-
Khafīyah, vol. 1. Jilid. 8. Beirut: al- Kutub al-Islamiyah, 1996.
Madjid, Nurcholish. Islam Agama Peradaban, cet. 1. Jakarta: Paramadina,
1995.
Mahrus, Syamsul Kurniawan dan Erwin. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan
Islam cet. 1 Jogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.
Ma‟arif, Ahmad Syafi‟I. Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia cet. 1
Bandung: Mizan, 1993.
Mohammad, Damami. Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka,
Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
Mukhlis. Inklusime Tafsir al-Azhar, cet. 1. Mataram: IAIN Mataram Press,
2004.
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2003.
Nizar, Ramayulis dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam: Telaah
Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, cet. 1. Jakarta:
Kalam Mulia, 2008.
Nizar, Samsul. Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran
Hamka Tentang Pendidikan Islam, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2008.
Qasimī, Muḥammad Jamᾱluddīn, al-Tafsīr al-Qᾱsimī al-Musammᾱ Mahᾱsin
al-Ta‟wīl, cet. 2. juz: 1-2 Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
Rahardjo Dawam, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, cet. 1.
Bandung: Mizan, 1993.
Rifai, Muhammad Nasib Ar-, Taisir al-aliyyul Qadir li Ikhtisar Taisir Ibnu
Katsir, Terjemahan Drs Syihabuddin, MA, Kemudahan dari Allah
ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1989
Razi, As-Syaikh al-Imam Muhammad bin Abi Bakr Ibn Abdul Qadir al-,
Mukhtar as-Shihah, Lebanon: Maktabah, 1980
87
Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Shihab M. Quraish. Sejarah dan Ulum al-Qur‟an,Vol 1, 5, 10, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2001.
-------. Tafsir Al-Misbah:Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur‟an. Jakarta:
Lentera Hati, 2009.
-------. Membumikan Al-Qur‟an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat Bandung: Mizan, 2013.
-------. Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur‟an. Bandung Mizan,
2000.
Shobahussurur. Mengenang 100 Tahun Haji Abdul Malik Karim Amrullah
(HAMKA), Cet 1 Jakarta: YPI Al-Azhar, 2008.
Susanto, A. Pemikiran Pendidikan Islam Jakarta: Amzah, 2009.
Tamara, Nasir. Hamka di Mata Hati Umat Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1996.
Al-Ṭabari, Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir. Jami‟ul al-Bayan „An Ta‟wil ayi
al-Qur‟an, juz. 19. terj. Ahsan askan. Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
Untung, M. S. Muhammad Sang Pendidik, cet.1 Semarang: Pustaka Rizki,
2005.
Yusuf, M. Yunan. Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, cet. 1 Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1990.
-------. Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas
Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam, cet. 1 Jakarta: Penamadani,
2003.
-------. Ensiklopedi Muhammadiyah, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005.