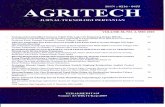Kajian Multidisiplin - UNIB Scholar Repository
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
Transcript of Kajian Multidisiplin - UNIB Scholar Repository
New Normal, Kajian Multidisiplin @ 2020
Editor : Akhsanul In’am & Latipun
Desain Sampul & Tata letak : Akhsanul In’am
Ukuran : 15.5 x 23 cm
Halaman : 583
© Penerbit Psychology Forum bekerjasama dengan AMCA
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Cetakan Pertama : September 2020
Akhsanul In’am & Latipun
New Normal, Kajian Multidisiplin
Malang: Psychology Forum, 2020
ISBN: 978-623-94285-2-5
Artikel dalam buku ini adalah sodakoh ilmu para penulis, jika anda
memerlukan, silahkan diperbanyak sesuai keperluan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | i
Sekapur Sirih
Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan perbincangan mengemuka untuk saat ini. Bukan hanya kasusnya yang baru terjadi, tetapi datangnya wabah ini telah mengubah pikiran, perasaan, perilaku dan segenap pola perilaku individu dan masyarakat. Sepanjang tahun 2020, energi kita difokuskan untuk dan dikaitkan dengan Covid-19. Tidak ada seorang pun yang luput perhatiannya terhadap Covid-19 ini.
Upaya mengatasi Covid-19 dipahami sebagai tugas bersama semua lapisan masyarakat, dengan segala upayanya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sepihak saja. Sebetulnya kalangan ilmuwan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan beban yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab itu karena dua hal. Pertama, ilmuwan memiliki pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Kedua, karena pengetahuannya itu, mereka memiliki kemampuan daalam memprediksi apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang ecara saintifik. Karena itulah, para ilmuwan ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menanggulangi persoalan kemasyarakatan, khususnya masalah Covid-19.
Pengetahuan tentang “Covid-19” belum dipahami mendalam dan tepat oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan wabah ini dapat kita pelajari dan dipahami, serta bagaimana cara mengatasinya. Informasi tentang hal tersebut mungkin dianggap tidak penting untuk saat ini karena sebagian orang merasa sudah tahu tentang apa yang dituliskan. Pengetahuan itu bukanlah untuk saat ini saja, tetapi juga diperlukan untuk beberapa tahun mendatang. Bahkan dalam kajian antropologi, pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan juga dipelajari setelah berabad-abad.
Tulisan para pakar AMCA yang dikemas dalam buku ini meru-pakan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suasana, pikiran dan perilaku masya-rakat dalam menghadapi wabah. Bermula dari tulisan-tulisan para pakar AMCA ini, terus dikembangkan telaah teoritik yang dalam jangka panjang dapat membantu masyarakat luas mengatasi masalah wabah kesehatan atau wabah lainnya.
Kami mengapresiasi para penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pengetahuan dalam konteks Covid-19. Semoga tulisan ini memberikan inspirasi bagi pembaca dan generasi
ii | New Normal, Kajian Multidisiplin
penerus kita, yang tentunya mereka ini akan menghadapi masalah dan tantangan kehidupan yang berbeda dengan yang kita alami.
Para pakar AMCA pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Kita semua masih akan berkarya, menulis dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak berguna. Artikel yang dituliskan dalam buku ini memberi manfaat yang tidak ternilai bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Assoc. Prof. Latipun, Ph.D. Sekretaris Jenderal Association of Muslim Community in ASEAN.
New Normal, Kajian Multidisiplin | iii
Daftar Isi
Sekapur Sirih
Daftar Isi
Editorial
Bagian Pertama Perspektif Agama Menyapa Pandemic Covid-19 Bab 1 Pengembangan Kompetensi Umat Islam di Tengah Covid-19
Abdul Muhith_3 Bab 2 Ketahanan Keluarga Perspektif Pendidikan Islam dalam
Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Akrim_17
Bab 3 Pandemi dalam Naskah Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn dan Naskah Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn Arwin_33
Bab 4 Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Organisasi Islam di Indonesia Rizka Harfiani_47
Bagian Kedua Kajian Pendidikan di era new normal
Bab 5 Psikologi Jawa: Menghadirkan Ajaran Lama Enem Sa dalam Kebiasaan Baru (New Normal) Tri Rejeki Andayani_65
Bab 6 Menggagas Edukasi Masyarakat Era New Normal Akhsanul In’am_75
Bab 7 Peningkatan Akurasi Tes Daring Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar di Masa Pandemi Covid-19 Bulkani_87
Bab 8 Kinerja Dosen dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi Covid-19 Heni Sukrisno_105
Bab 9 Eksplorasi Geografi Emosi Guru dalam Mengelola Kelas Daring Selama Pandemi Covid-19 Khoiriyah dan Fathur Rohman
Bab 10 Pelaksanaan Kegiatan KBM online di Sekolah Vokasi IPB Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan pada Masa Covid dan New Normal Lili Dahliani_137
Bab 11 Pandemic COVID 19 Mengembalikan Pendidikan dalam Keluarga Munawir Pasaibu_151
ii | New Normal, Kajian Multidisiplin
Bab 12 Pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning Solusi dan
Aksi Pembelajaran di Era New Normal Pandemi Covid 19 Nurul Zuriaah
Bab 13 Problematika Literasi Matematika yang dihadapi Guru dan Siswa pada Sekolah Berbasis Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Umi Farihah, Dimas Danar Septiadi, Arik Hariati_189
Bab 14 Menakar Kesejahteraan Subjektif Guru pada Masa Adaptasi Baru Erita Yuliasesti Diah Sari, Iqhsan Eko Setiawan_211
Bagian Ketiga Tinjauan Hukum di masa Covid-19
Bab 15 Implementasi Nilai-Nilai Moral Pancasila dan Perubahan Perilaku di Era Pandemi Covid-19 Abustan_225
Bab 16 “Jogo Tonggo”: Suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penangan Covid19 sebagai Wujud Rekayasa Hukum Lita Tyesta ALW; Adissya Mega Cristia241
Bab 17 Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19; Tinjauan Psikologi Hukum Sudjiwanati
Bab 18 Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Lingkungan Keluarga di Era Pandemi Covid 19 Supriatnoko_277
Bab 19 Polemik Keputusan Pemberhentian Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya Zainal Abidin Achmad_299
Bagian Keempat Menggagas kesehatan menanggulangi covid-19
Bab 20 Kelor (Moringa Oleifera), Penguat Imun Tubuh di Masa Pandemi Covid-19 Eny Dyah Yuniwati_319
Bab 21 Sirup Daun Jambu Air Sumber Anti-oksidan Fadjar Kurnia Hartati_331
Bab 22 Produksi Hand Sanitizer Di Tengah Kelangkaannya selama Pandemi Covid-19 Di Lingkungan IAIN Jember A. Suhardi, Laila Khusnah, Laily Yunita Susanti, Rafi’atul Hasanah_349
New Normal, Kajian Multidisiplin | v
Bab 23 Food Estate: Mewujudkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi
dan Pasca Pandemi Covid-19 Sutawi_365
Bagian 5 Perspektif Budaya Menjawab Tantangann Covid-19
Bab 24 Senandung Wacana “Mantra Wedha” Sebagai Kearifan Lokal Etnik Jawa: Sebuah Model Alternatif Penangkal Covid-19 Dwi Bambang Putut Setiyadi_383
Bab 25 Reformulasi Nilai karakter dalam Pembelajaran Daring di Era Pandemi Untuk Mencegah Fraud Academic Endah Andayani_399
Bab 26 Pembelajaran Bahasa Indonesia Berorientasi Kecakapan Hidup bagi Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19 Daroe Iswatiningsih_411
Bab 27 Covid-19 dan Perilaku Berbudiutama Nurcholis Sunuyeko, Rochsun, Harun Ahmad_427
Bab 28 Peningkatan Kepuasan Kerja Berbasis Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Nurul Qomariah dan M. Sulton_443
Bab 29 Kepemimpinan dan Kenormalan Baru Pieter Sahertian_459
Bab 30 Wacana Pagebluk Covid-19 pada Masyarakat Jawa: Kajian Register Prembayun Miji Lestari, Retno Purnama Irawati, Agus Yuwono_475
Bagian Keenam, Kajian ekonomi bertahan pada pasa covid-19
Bab 31 Sustainability Inovasi UKM di Masa Pandemi Asngadi dan Mas’adah_487
Bab 32 Hentakkan Kata Merdeka Pemberdaya Masyarakat Masa Pandemi Covid 2019 Dian Eka Chandra Wardhana_503
Bab 33 Strategi Bertahan Pedagang Pasar di Masa Pandemi Covid 19 Endang Sungkawati_529
Bab 34 Himmatul ‘Amal Dalam Ekonomi Islam Saat New Normal A. Ifayani Haanurat_545
Bab 35 Lonjakan Gugatan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Apakah Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Utamanya? Mochamad Ridwan_559
New Normal, Kajian Multidisiplin | vii
Editorial
Dunia selalu berubah dan yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Hukum itulah yang hendaknya dipahami dan dapat dijadikan dasar dalam menata diri dan hati untuk melangkahkan kaki dan pikiran dalam mengarungi samudra perhelatan tatanan kehidupan di dunia. Pandemi covid-19 yang melanda kehidupan manusia, dan hampir seluruh permu-kaan bumi tiada yang luput dari datangnya makhluk Allah yang tak nampak mata namun berdampak sangat luar biasa.
Segala segi tatanan dan aturan dalam berinteraksi yang selama ini dapat dikatakan dalam kondisi normal, semuanya menjadi tatanan yang tidak biasa. Secara mantuq, ketika manusia berinteraksi dengan yang lain sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan harus ada pemaksaan, untuk selalu menggunakan masker. Namun hal tersebut dapat juga dimaknai secara mafhum, boleh jadi disebabkan oleh kebiasaan manusia yang bicaranya tidak dapat mengindahkan yang lain bahkan cenderung saling menghujat, hendaknya dalam masa pandemi ini sudah sepaturnya menahan diri dan hanya menyampaikan dengan cara yang santun dan baik. Kondisi ini bukan mengada, namun jika diperhatikan, tiada sedikit manusia saling berkata yang tidak elok, dan juga boleh jadi saling menjatuhkan yang disebabkan hanya untuk kepentingan dunia semata. Hanya untuk kepentingan tertentu, ada sebagian yang rela menyampai-kan kata-kata yang menyakitkan sesamanya. Jika ingat pesan Rasulullah, wahai orang-orang yang meyakini adanya hari akhir, berkatalah kamu dengan baik, namun jika tidak dapat menjaga yang demikian lebih baik engkau diam. Fakta yang ada hujat menghujat, saling menyerang dengan kata sudah bukan sesuatu yang enggan dilakukan, bahkan boleh dikatakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Demikian juga dalam aktivitas yang dilakukan hendaknya selalu menjaga kebersihan melalui kebiasaan mencuci tangan. Ditinjau dari sisi kesehatan, virus akan pergi melalui cuci tangan dengan sabun dengan cara sebagaimana disarankan. Namun hal itu merupakan sesuatu yang tersurat dalam melaksanakan aktivitas. Namun makna tersiat sesung-guhnya sangat dalam pengertiannya. Tangan cukup dicuci dengan sabun sudah bersih, namun hati meminta agar ikut serta disucikan. Terjadinya pertikaian dan pertengkaran tiada lain karena adanya titik hitam yang menggerogoti niat untuk berbuat yang tidak berkenan. Titik noda hitam dalam kalbu sangat mempengaruhi tindakan dan arahan dalam melak-sanakan suatu kegiatan. Lantas apa yang seharusnya dilakukan? Ambilah air untuk mencuci tangan dengan tiada lupa mensucikan diri
ii | New Normal, Kajian Multidisiplin
melalui ritual wudu (bersuci), dan senyampang bersuci ikhlaskan hati untuk mensucikan kalbu agar tertoreh niat yang suci dalam mengemban titah Illahi. Kalbu yang suci menjadikan aktivitas menjadi tertata dan rapi sesuai ketentuan Illahi, tiada niat menjegal bahkan menendang kawan, bahkan jika ada aral yang melintang, taida segan ikut menyingkarkan agar kita memperoleh keberkahan yang berlipat. Sesiapa yang membantu meringankan beban yang lain, dengan berkata baik, menghilangkan aral yang melintang dari aktivitas kawan, maka yang demikian termasuk sedekah, dan Allah akan memberikan balasan kepada siapa saja yang bersedekah dengan balasan sebanyak 700 kali lipat (QS 2: 261). Firman tersebut sebagai motivasi kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik, dalam perkataan maupun perbuatan sehingga kehidupan menjadi tenteram.
Interaksi yang terjadi sebelum masa covid boleh jadi merupakan bentuk kedekatan antar insan dalam menjalankan amanah. Duduk berdekatan membincangkan permasalahan adalah hal yang wajar sebe-lum masa pandemic covid-19. Namun kondisi sekarang semuanya ber-ubah, usaha untuk tidak saling memberikan dampak dengan adanya virus corona, jaga jarak dalam berinterkasi merupakan suatu keharusan. Melalui saling jaga jarak bermakna saling membantu agar terbebas dari virus yang tiada dikehendaki. Secara tersurat, memang salang jaga jarak merupaka keharusan dalam menjaga kesehatan dimasa pandemic-covid 19, namun dibalik itu semua ada hal yang sesungguhnya pelajaran yang sangat bermakna. Mari saling introspeksi, sebagaimana dikatakan Umar bin Chotob, r.a. koreksilah dirimu terlebih dahulu sebelum mengoreksi yang lain. Hal terbaik yang hendaknya dilakukan, tengoklah diri sendiri sebagai usaha untuk memperbaiki diri, dan memang melihat kekurangan orang lain lebih mudah berbanding melihat kesalahan yang kita lakukan, semut di seberang lautan nampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak.
Tiada sedikit dalam interaksi sehari-hari sangat dekat dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Illahi Yang Maha Tinggi. KH Mustofa Bisri, menyindirnya dengan puisi yang sangat menyentuh.
Di negeri Amplop Aaladin menyembunyikan lampu wasiatnya, Malu Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi Dacid Copperfiled dan Houdini bersembunyi rendah diri Entah andaikata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya Amplop-amplop di negeri Amplop Mengatur dengan teratur, hal-hal tak teratur menjadi teratur hal-hal teratur menjadi tak teratur
New Normal, Kajian Multidisiplin | ix
memutuskan putusan yang tak putus membatalkan putusan yang sudah putus Amplop-amplop menguasai penguasa Dan mengendalikan orang-orang biasa Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan Mencairkan dan membekukan, Mengganjal dan melicinkan Orang bicara bisa bisu Orang mendengar bisa tuli Orang alim bisa napsu Orang sakit bisa mati Di negeri Amplop Amplop-amplop mengamplopi Apa saja dan siapa saja (Gus Mus) Mari mencoba mengaca diri, adakah diantara bait-bait puisi Gus
Mus menyindir kita, bagaimana dengan lingkungan dimana interaksi keseharian menjadi kegiatan rutin yang dilakukan ada hal sebagaimana bait indah Gus Mus. Tidak perlu menuduh dan mengeluh, seandainya hal tersebut ada disekitar dimana interaksi menggelayuti tatanan yang ada, sudah seyogyanya dihindari dan tidak diimplementasikan.
Disinilah makna tersembunyi kita harus menjaga jarak dalam menjalani masa pandemic covid-19. Mulailah menjaga jarak, janganlah yang sudah dilakukan sebagaimana hal tersebut diteruskan. Semua ada batasnya, segala kesalahan dapat ditebus dengan menghapus segala kekhilapan dengan tidak mendekati, apalagi melaksanakan segala yang tidak diperintahkan.
Kumpulun tulisan dalam buku ini, hasil refleksi dari berbagai disiplin keilmuan, sebagai salah satu keprihatinan para pakar dalam menghadapi masa pandemic covid-19. Ulasan dan paparan yang ada dapat bermakna tersurat maupun tersirat, mantuq dan juga mafhum, yang semuanya bermuara, agar dalam menjalani titah dan perintah Maha Tinggi, dapat dijalani dengan sepenuh hati dan dapat menjaga diri agar, perjalanan menggapai RahmatNya dapat terwujud tanpa luput, hidup penuh bahagia didunia, dan selamat dari segala rintangan yang menghalangi serta memperoleh RidloNya dalam menapaki masa yang tak bertepi serta penuh hakiki.
Malang, September 2020 Prof. Akhsanul In’am, Ph.D.
Presiden AMCA Indonesia
New Normal, Kajian Multidisiplin | 3
Bab 1
Pengembangan Kompetensi Umat tentang Islam di Tengah Covid-19 Abd. Muhith & Amirul Wahid RWZ1
Pengantar COVID-19 merupakan fenomena baru yang pertama kali muncul di
Kota Wuhan Provinsi Hubei China [1], walaupun menurut Gao Fu, Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit China, bahwa Virus Corona bukan berasal dari Pasar Wuhan. Jumlah kasusnya hingga 25 Agustus lalu sudah mencapai 24 juta kasus tersebar di seluruh dunia dengan negara terpapar paling parah yakni Amerika, Brazil, dan India. [2] Hingga saat ini, belum dapat dipastikan adanya titik terang solusi berupa obat ataupun vaksin yang terbukti ampuh menghempas peredaran virus.
Seluruh negara terpapar berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan penanganan terhadap kasus ini. Beberapa malah berlomba-lomba menunjukkan kapasitas negaranya sebagai negara yang tangguh dalam kondisi apapun. Konteks yang dilombakan adalah upaya penanganan virus terhadap warga terpapar, penemuan vaksin atau obat untuk COVID-19, dan ketangguhan aspek kehidupan bernegara dari segi administrasi hingga ekonomi. Semua ini dilakukan atas dasar ke-manusiaan, manusia yang berjuang untuk menjaga keberlangsungan kehidupan mereka agar terus lestari tanpa gangguan virus apapun.
Dewasa ini, COVID-19 telah dipahami sebagai suatu pandemi. Hal ini mengacu terhadap pernyataan Direktur Jenderal Lembaga Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menurut detikhealth, pandemi merupakan suatu penyebaran penyakit dalam tingkat global atau dengan kata lain di atas epidemi. [3] Pandemi yang terjadi saat ini bisa dikatakan cukup parah jika dibandingkan dengan beberapa pandemi lain yang pernah mengguncang dunia sebelumnya. Sebabnya, wabah penyakit yang dibawa oleh pandemi saat ini berpengaruh terhadap kehidupan vital manusia secara lebih luas. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia terkendala. Dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan birokrasi di setiap negara juga terkena imbasnya. Demikian, maka setiap orang baik yang sudah terpapar atau yang tidak terpapar
1 Dr. Abd. Muhith & Amirul Wahid RWZ, Dosen IAIN Jember
4 | New Normal, Kajian Multidisiplin
diwajibkan untuk bersikap cekatan dalam mengantisipasi resiko-resiko yang kemungkinan dapat terjadi dan menyerang mereka.
Maksud dari Langkah antisipatif tersebut adalah untuk melatih bertahan hidup dalam keadaan yang sulit. Seorang manusia yang telah terpapar akan sulit baginya untuk tetap bersikap besar. Saat ini, kita tidak seharusnya terus menerus menggantungkan nasib kita terhadap negara. Apa yang kita harapkan dari seseorang yang juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Langkah solutif dan antisipatif yang kita perlukan sebagimana penjelasan dalam paragraf sebelumnya adalah bagaimana diri kita benar-benar dapat mengambil langkah tepat untuk kemasalahatan diri kita sendiri atau lebih baik jika untuk kemaslahatan bersama. Langkah tersebut dalam aspek mana saja. Tidak harus melulu dalam penerapan protokol kesehatan. Karena pandemi yang bersifat universal ini, maka terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan agar supaya tercipta harmonisasi keseimbangan kehidupan manusia.
Salah satu permasalahan yang terjadi pelik di Indonesia adalah kontroversi penerapan kehidupan beragama bagi masyarakat lebih-lebih bagi umat muslim. permasalahan ini dibagi menjadi dua konteks yakni konteks kehidupan beragama dalam keadaan pandemi dan pelaksanaan syari’at yang dibenarkan. Keduanya memiliki alasan masing-masing mengapa menjadi sebuah topik yang urgen untuk dibahas lebih lanjut. Alasan yang terjadi di masyarakat lebih mengarah terhadap permasalahan kontekstual yang menuntut solusi tepat dan efisien dengan pelaksanaan secepatnya.
Konteks kehidupan beragama pada masa pandemi kali ini adalah suatu pembahasan terhadap peran agama sebagai pedoman hidup manusia secara fundamental. Pasalnya, kehidupan manusia yang selalu dinamis membuat kebutuhan dirinya selalu berbeda dan terus berubah-ubah. Apalagi saat pandemi, kegamangan, kebingungan, dan kemero-sotan dalam hidup bisa saja membuat seseorang menjadi patah arang lalu melakukan hal yang tidak tidak. Bukan tidak mungkin seseorang yang ketika hati dan pikiranya sedang kacau justru melakukan perilaku maksiat sebagai langkah pelarian dari masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Oleh karena itu, dalam hal ini agama memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan wawasan atau arahan terhadap setiap golongan manusia agar tetap berjalan pada koridor yang benar.
Selanjutnya ialah dalam penerapan pelaksanaan syariat umat Islam. Islam adalah agama moderat yang menghargai dan sangat menghormati perbedaan yang terjadi dalam sebuah peradaban manusia.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 5
Perbedaan yang dimaksud bersifat kompleks. Misalnya dalam pem-bahasan tekait syari’at, ulama’ atau mujtahid dalam bersyari’at memiliki perbedaan pandangan atau ajaran yang sangat beragam. Para imam mujtahid yang kita kenal ada 4 (Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi,) masing-masing memiliki jalan yang berbeda terhadap suatu hukum syari’at. Namun perbedaan tersebut bukanlah pemecah umat muslim untuk saling bermusuhan atau saling sikut antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini senantiasa menjadi rahmat bagi setiap muslim sekalian untuk menjadi opsi syari’at mana yang paling cocok untuk mereka terapkan dalam kehidupan pribadi mereka. Pemahaman ini yang seringkali disalah artikan oleh beberapa golongan yang ‘membeda’.
Demikian, kehidupan beragama dan pelaksanaan syari’at adalah bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang muslim terlebih pada saat keadan genting akibat COVID-19 ini. Keduanya sangat penting untuk menjadi wawasan wajib umat muslim guna mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu permasalahan bahkan yang lebih besar dari sekedar pandemi ini. Oleh karena itu, penulis berinisiasi untuk memberikan orientasi tersebut agar dapat dipetik nilai hikmah untuk kemaslahatan umat sekalian. Di kala pandemi seperti sekarang, muslim Indonesia atau bahkan seluruh dunia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih religius dan mendekatkan diri kepada sang Pencipta lebih dari masa-masa sebelumnya. Terkadang, suatu musibah yang diturun-kan tuhan kepada manusia bukanlah untuk menjerumuskan manusia kepada lubang kesengsaraan melainkan semata-mata sebagai self-reminder agar manusia selalu ingat bahwasanya terdapat kekuasaan yang lebih agung dari apapun.
Pembahasan
Agama Islam
Pemahaman lebih mendalam terhadap agama Islam menjadi pembuka diskursus pengembangan kompetensi umat. Dalam pema-haman empiris, manusia sangat dianjurkan untuk pertama kali mengerti apa yang ia pelajari. Sama halnya dengan Islam. Islam adalah sesuatu (agama) yang dibawa oleh Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyunya. Wahyu berbentuk Al-Qur’an tersebut yang kemudian disampaikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Penalaran terhadap Islam sebagai agama dan pedoman hidup wajib dilakukan oleh sebuah
6 | New Normal, Kajian Multidisiplin
studi komprehensif yang berkaitan. Hal ini bertujuan untuk penyajian manifestasi Islam yang sesungguhnya.
Agama Islam memiliki tiga komponen yaitu aqidah, syari’at dan akhlak, ketiga komponen tersebut pernah diajarkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. di saat beliau duduk bersama sahabatnya, pembelajaran tentang ketiga komponen tersebut dilakukan dengan metode tanya jawab, sebagaimana paparan hadits berikut:
Yang artinya: Ibnu Umar berkata: “Umar Bin Khttab Ra. Berkata: “Ketika suatu hari kami duduk di sisi Rasul Saw. tiba-tiba muncul suarang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat jejaknya, dan tidak seorangpun di antara kita mengenalnya, siapa dia hingga ia duduk rapat dengan Rasulullah Saw. lalu kedua lututnya bersandar pada kedua lutut Rasulullah Saw. dan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul saw. kemudian ia berkata: “Beritakan kepadaku tentang Islam!”, lalu Rasulullah Saw. menjawab: “ Islam adalah engkau harus bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan puasa ramadlan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu”, lalu ia berkata: “Engkau benar”, kami heran padanya, ia yang bertanya lalu membenarkannya”, Umar berkata: “lalu ia berkata: Beritakan kepadadaku tentang iman!”, Rasulullah menjawab: Iman adalah engkau harus yakin kepada Allah, malaikat, kitab suci, para utusan, hari kiamat dan semua hal yang baik dan buruk dari Allah”, ia berkata: ‘Engkau benar’, lalu ia berkata: “Ceritakan kepadaku tentang ihsan, apa ihsan itu?”, lalu nabi menjawab: “Engkau harus beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, jika tidak mungkin melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. [4]
Hadits di atas dapat dianalisis sebagai dasar umat Islam menghadapi berbagai persoalan, termasuk pandemi COVID-19 dan new normal, karena ketika umat memahami tiga komponen ajaran agama Islam tersebut, umat dapat dipastikan memiliki pemahaman dan sikap yang luwes dalam menghadapi persoalan. Ketika memahami arti keimanan dan nilai-nilainya, maka ia akan siap menghadapi kondisi apapun, karena semua yang terjadi berjalan sesuai dengan takdir Tuhan akan tetapi tetap mengikuti aturan main yang berlaku, karena memahami rukun Islam yang lima tentu akan menyiapkan berbagai perangkat yang menyertainya serta menyesuaikan dengan kondisinya. Demikian pula ketika umat memahami arti dan nilai ihsan, mereka tidak akan arogan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 7
merespon persoalan, karena seluruh aktivitasnya senantiasa di awasi oleh Allah SWT.
Berkaitan dengan itu, fenomena yang timbul di masyarakat selama pandemi ini kian beragam. Beberapa pihak malah terlihat tidak menampakkan keluwesan dirinya padahal ia adalah seorang muslim. Sejak diumumkanya situasi pandemi dan banyaknya korban jatuh berguguran, sebagian masyarakat menjadi panik dan kebingungan untuk meneruskan laju kehidupan mereka. Kepanikan yang melanda membuat mereka berada pada sebuah pilihan yang sulit. Ingin mereka bekerja dan mencari nafkah untuk makan di hari ini dan esok namun rasanya tidak mungkin karena harus menerapkan social distancing yang sangat mempersulit. Namun jika mereka tidak kerja maka tak ada lagi makanan untuk esok, untuk menyambung hidup.
Menghadapi persoalan tersebut, sebagai muslim yang bijak kita seharusnya mengambil jawaban dari apa yang telah diajarkan oleh agama kita sendiri. Meninggikan dzat Allah pada posisi yang paling tinggi dalam tataran kehidupan seluruh mahluk yang ada adalah jawaban. Corona semengerikan apapun tetap merupakan ciptaan Allah dan semua ciptaan Allah selalu diciptakan atas alasan dan dasar tertentu. Rahasia ilahi yang tidak diketahui siapapun ini seharusnya dapat membuat kita sebagai umat manusia ber-khusnudzon terhadap apa-apa yang telah Ia kehendaki. Mungkin saja, Allah ingin mengingatkan manusia-manusia yang telah lalai dari perintah awalnya pindah ke bumi yakni untuk menjadi khalifah dari setaip mahluk. Sehingga kita dapat membuat momen pandemi ini sebagai momen evaluasi akan sesuatu yang telah kita perbuat sebelumnya. Jelasnya, kita harus merubah kepribadian kita dari yang tidak seharusnya menjadi perilaku yang sesuai dengan syari’at agama. Tidak perlu merasa risau dengan konflik-kondlik duniawi yang timbul. Apabila kita berpasrah terhadap Dzat yang menciptakan maka semuanya akan berjalan dengan semestinya. Baik buruknya kehidupan manusia bukanlah dinilai oleh manusia yang lain melainkan langsung dengan penilaian tuhan.
Iman
Iman menurut hadits adalah percaya akan adanya Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari kebangkitan, dan kepastian allah. Sedangkan menurut pendapat ulama, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan membutikan dengan perbuatan. [5] Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat digali nilai-nilai keimanan secara menyeluruh, yang intinya orang yang
8 | New Normal, Kajian Multidisiplin
beriman senantiasa berkata benar, sesuai dengan hati nurani dan senantiasa apa yang dikatakannya selaras dengan perbuatannya. Dalam kondisi apapun termasuk pada saat pandemi dan new normal, orang beriman tidak akan gegabah mengeluarkan statement yang dapat memancing amarah, hatinya tulus menerima informasi terbaik dan aktivitasnya tidak arogan, ia bersahaja, tenang dan dapat membuat orang lain dan lingkungannya tenteram.
Orang yang beriman tidak pernah menafikan keberadaan Allah dalam setiap kejadian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an, Surat At-Taubah yang artinya berikut ini:
Katakannya…tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah dituliskan oleh Tuhanku, dan kepada Allah hendaknya orang-orang beriman berpasrah diri.” [6]
Ayat tersebut awalnya diturunkan agar Rasulullah saw. tidak putus asa menghadapai kekalahan di perang uhud, karena semua terjadi atas kehendak Allah yang tak bisa dirubah, demikian itu merupakan sanggahan terhadap ungkapan orang munafik yang menghina kekalahan yang menimpa kaum muslimin pada saat itu. Dalam kondisi apapun kaum muslimin tidak akan pernah menggerutu menerima kondisi apapun yang telah ditakdirkan Allah, ia akan menghadapinya secara mengalir, karena apaupun yang terjadi pastilah yang terbaik, sebagaimana hadits nabi yang artinya sebagai berikut:
dari Jabir Bin Abdillah dia berkata: “ Ralulullah Saw. bersabda: “Seorang hamba tidak beriman sehingga ia meyakini kepastian Allah sampai ia memahami bahwa apa yang menimpanya tidak akan membuatnya salah dan apa yang membuatnya salah tidak akan pernah menimpanya.” [7]
Seorang yang benar-benar memahami arti dan nilai keimanan dan ajaran tentang keimanan, ia tidak akan pernah galau, karena takdir Allah tidak pernah sia-sia. Keimanan atau keyakinan merupakan pondasi yang menjadi sahnya ibadah dan akhlak atau prasyarat dari Islam dan Ihsan, Iman tidak bisa ditawar atau setengah hati Karena lawan kata Iman adalah syirik, sedangkan orang yang ambigu dengan keimanannya disebut munafiq. Iman juga disebut dengan aqidah, sehingga jika aqidahnya sesat, maka ibadahnya tidak sah.
Berkaitan dengan penjelasan di atas, pengamalan iman pada saat pandemi juga penting untuk dibahas. Kini, ketika masyarakat dibuat panik karena terus naiknya jumlah pasien yang terpapar, ketakutan terhadap virus seakan-akan melebihi ketakutan mereka terhadap siapa yang menciptakan virus. Memang sulit sekali untuk menyikapi suatu konflik yang kita hadapi didepan mata kita selagi kita bersikukuh dengan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 9
prinsip yang kita peang. Corona adalah virus nyata yang tak kasat mata namun eksistensinya selalu menghantui kita. Pemikiran-pemikiran yang berlebihan terhadapnya tidak bisa dipungkiri selalu menyerang psikis kita. Pada saat demikian, teorema iman harus kita sisipkan dalam pemikiran kita. Jangan sampai kehawatiran kita melebihi ketakutan kita pada sang empunya semesta.
Langkah yang bisa kita ambil adalah tetap membatasi kekha-watiran tersebut dengan menggantinya dengan kewaspadaan. Waspada berarti kita tetap mawas diri dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah sementara dalam hati kita tetap selalu percaya bahwa jik kita bertaqwa dan selalu meminta aman dalam perlindunganNya maka kita kesehatan insyaallah akan selalu bersama kita. Secanggih atau sehebat apapun penyebaran virus ini jika kehadiranya tidak dikehendaki untuk merongrong raga kita oleh sang Kuasa maka kehadiranya juga mustahil. Kompetensi keimanan yang seperti ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim agar ia terhindar dari pelbagai kekhawatiran akan sesuatu yang berlebihan. Baik saat pandemi ataupun di luar pandemi.
Islam
Islam dipahami dari hadits di atas, merupakan keharusan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa ramadlan dan haji bagi mereka yang mampu. Sedangkan Islam menurut ulama, merupakan kepatuhan dan tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Secara harfiyah Islam berarti mendamaikan atau tunduk, pada dasarnya orang Islam tunduk pada kebenaran dan aturan yang tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam, bahkan senantiasa menciptakan kedamaian baik di saat normal atau new normal.
Berislam dalam topik yang dimaksudkan ialah melaksanakan syari’at Islam ansikh bukan beraqidah, sehingga Islam sebagai syari’at adalah kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan berupaya meninggalkan larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta kemampuan, sehingga hal tersebut dapat dilakukan sesuai tiga asas penerapan syari’at yaitu bertahap (تدريج), tidak menyulitkan (عدم الحرج), dan menyedikitkan hukum (تقليل الحكم). [8] Penerapan syari’at Islam dilakukan secara bertahap artinya, dimulai sedikit demi sedikit, dari yang sederhana hingga yang kompleks, hal tersebut dapat dilakukan dengan pembiasaan sehingga tidak terkesan
10 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menekan atau memaksa, menggunakan skala prioritas, dengan mengutamakan kewajiban individu (الفروض العينية), lalu kewajiban bersama yang ,(السنة) anjuran ,(السنة المؤكدة) anjuran yang dikokohkan ,(الفروض الكفاية)diperbolehkah )المباح(, meningalkan yang haram (المحرمات), lalu meninggalkan yang tidak disukai (مكروه), dan meninggalkan yang tidak ada manfaatnya (خالف االولى). [9] Sedangkan penerapan syari’at secara tidak menyulitkan artinya sesuai dengan kemampuan manusianya, karena Allah tidak pernah membebani seseoang di luar kemampuannya. [10] Tidak ada tekanan atau dengan cara radikal, karena hakikat da’I, kyai, guru adalah hanya sebatas menyampaikan informasi, pemberi pelajaran, menasehati, membimbing dengan kasih sayang sebagaimana nilai yang terkandung dalam basmalah, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dalam penerapan syari’at Islam ada kondisi normal dan kondisi darurat. Dalam kondisi normal, Islam memberi prinsip penerpannya sebagaimana tersebut di atas, dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan syari’at Islam yaitu, menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa ( حفظ
) menjaga akal ,(النفس حفظ العقل ), menjaga harta (حفظ المال), dan menjaga keturunan (حفظ النسل). [11] Sedangkan penerapan syari’at Islam dalam kondisi darurat atau diduga dalam keadaan sulit, bisa menyesuaikan dan bahkan terdapat kemudahan yang bisa meninggalakan kewajiban dan melanggar aturan dengan syarat-syarat tertentu, karena kondisi darurat dapat memperoleh keringanan (المشقة تجليب التيسير). [12]
Melihat betapa luwesnya Islam sebagai suatu pedoman dalam bersyariat, maka sebaliknya banyak sekali kini yang masih belum mengerti tentang penerapanya. Baik saja jika mereka yang tidak tau mencari tau dengan belajar kepada seorang ahli, berguru kepada mereka dengan menimba ilmu. Sayangnya orang dengan pengetahuan minim akan syari’at tersebut justru seakan menggururi umat. Mereka membuat suatu penjelasan tentang syari’at yang didalamnya tidak ada tendensi terkait serta tidak dilandasi dengan pondasi syari’at yang dapat dibenarkan. Di tengah digitilisasi dunia saat ini, informasi yang mereka sebarkan melalui sosial media menjadi sangat cepat tersebar. Padahal tanggapan yang diberikan bersifat arogan dan menjustifikasi, tidak dianalisis secara terbuka, tidak rasional dan tidak menggunakan kaidah syari’at Islam, serta prinsip, dan tujuan penerapannya belum jelas karena tidak menggunakan paradigma yang ideal. Maka dengan hadirnya ulasan tersebut di atas, secara tidak langsung menunjukkan betapa lunaknya Islam sebagai agama. Tidak ada keharusan yang kaku dalam
New Normal, Kajian Multidisiplin | 11
Islam kecuali bagi mereka yang mempersulit keadaan dan tidak mau mencari kebenaran yang hakiki.
Islam dalam pembahasan ini, dikaitkan dengan dimensi Iman yaitu ibadah sehingga orang yang mengamalkan syari’at Islam disebut orang yang taat, sedangkan orang yang tidak melakukan syari’at Islam disebut ma’siat, ma’siat tidak sama dengan syirik senyampang seseorang masih meyakini keberadaan syari’at tersebut dan mengakui pelanggarannya terhadap syari’at karena ketidakberdayaan melawan nafsu dan godaan setan.
Secara fundamental, antara syari’at dan new normal sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali bahkan keduanya saling berkesinambungan. Pada awal pelaksanaan kebijakan new normal banyak sekali umat yang kalang kabut atas bagaimana mereka melaksanakan laku ibadah dalam keadaan yang seperti ini. Sholat Jum’at, sholat berjamaah, dan melaksanakan haji saat penerapan physical distancing adalah beberapa contoh ibadah dalam agama yang bersifat kolektif. Beberapa golongan kaum muslimin di Indonesia bahkan sampai menolak penerapan pembatasan jarak fisik lantaran tak ingin mengurangi keutamaan ibadah kolektif mereka. Sebagian yang ekstrim bahkan juga tidak tanggung-tanggung mengecam kebijakan pemerintah tersebut. Mereka tidak menaruh kepercayaan terhadapnya dan berpikir bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah saja untuk melancarkan suatu rencana terselubung dengan membuat kepanikan dalam masyarakat.
Padahal hal tersebut justru bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Islam sebagai agama moderat yang sangat menghargai perbedaan, selalu mengedepankan kepentingan darurat dari pelaksanaan syari’at sekalipun. Tidak ada pemaksaan untuk melanggar tatanan yang berlaku. Konyolnya, bahkan ketika sudah ditasbihkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya terdapat sebuah hukum yang telah menjelaskan tentang itu justru tidak digubris oleh jemaat yang sengaja mengadu domba masyarakat dan pemerintah. Mereka seakan mengacuhkan himbauan dan keterangan dari MUI tersebut untuk kebutuhan pribadi atau golongan khusus mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masayarakat. Mereka sengaja membangun citra tersebut bahwa pemerintah mempunyai stigma negatif yang sangat tinggi hingga akhirnya masyarakat tidak menaruh kepercayaan terhadap pemerintah.
12 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Keterangan yang disebutkan dalam fatwa MUI No. 31 Tahun 2020
tentang shalat Jum’at dan berjamaah bahwa muslim yang beribadah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tidak akan kehilangan kesahan serta keutamaan ibadah mereka.[13] Hal ini disebabkan bahwa untuk menghindari transisi virus yang tak kasat mata maka model ibadah yang tepat harus dilaksanakan karena bersinggungan dengan hajat syar’iyyah. Beberapa pihak menyebut pelaksanaan syari’at saat ini sebagai ‘fiqh pandemi’. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak perlu merisaukan ibadah mereka.
Sebagai seorang muslim yang bijak, kita seharusnya bersikap selektif terhadap suatu kebijakan. Hilangkan egosentris pribadi dan golongan tertentu karena itu hanya akan menimbulkan konflik tak berkesudahan. Seperti halnya pelaksanaan syari’at ini. Pemerintah dalam memberlakukan kebijakan apalagi dalam suatu hal yang pelik dan sensitif seperti agama pastinya tidak sembrono dengan main asal comot hadits sana sini. Pertimbangan matang oleh para ulama terpilih seperti MUI pasti sudah dilaksanakan. Hal ini ditujukan dalam rangka membina keharmonisan warga negara dalam pelaksanaan ibadahnya secara individual maupun yang bersifat kolektif. Cuitan dari berbagai penjuru memang lumrah terjadi, sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah memperjelas arah haluan kita. Tendensi atau landasan mana yang harusnya kita ambil.
Ihsan
Ihsan merupakan perilaku terbaik, karena orang yang telah memahami Ihsan maka ia akan selalu merasa diawasi Allah, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Ia merasa senantiasa dinilai, dan mencari alternatif terbaik yang tidak membuat makhluk lain tersakiti, menerapkan Islam lebih banyak menggunakan hati nurani yang tidak dapat dibohongi. Hal tersebut dianalisis dari untaian hadits yang artinya berikut:
Dari Nuas Bin Sim’an al-Anshari, ia berkata:”saya bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang kebaikan dan keburukan”, lalu Ralullah menjawab: “Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang yang berdebar di dadamu dan engkau tidak suka diketahui manusia.” [14]
Dari uraian singkat tentang Ihsan, jelas bahwa Ihsan adalah mencari cara terbaik untuk melaksanakan sesuatu. Cara terbaik tersebut kemudian disebut dangan akhlak, sedangkan akhlak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu akhlak kepada Tuhan YME, akhlak kepada diri sendiri dan dan akhlak kepada makhluk lain. Orang yang mengamalkan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 13
Ihsan disebut dengan orang yang baik akhlaknya sedang orang yang tidak mengamalkan Ihsan disebut orang yang buruk akhlaknya.
Kompetensi ihsan tersebut di atas jika diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan menciptakan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan tentram. Meski tidak semua masyarakat Indonesia adalah seorang muslim, namun hal ini tidak menampik bahwasanya umat muslim yang mayoritas dapat memberikan teladan serta manfaat yang baik terhadap lingkungan mereka. Teladan tidak perlu dilakukan secara kolektif, ia dapat dimulai dari kesadaran masing-masing individu untuk bersikap baik dan ramah terhdap siapapun berdasarkan pengamalan kompetensi-kompetensi yang telah tersusun.
Sebut saja ketika keadaan new normal ini. Kita boleh saja memiliki prersepsi terhadap kemunculan Corona dan segala sesuatu yang timbul akibatnya (misalnya, rapid test, swab test, pembatasan sosial, dll) namun dalam bernegara kita harus tetap mendukung serta melakukan anjuran pemerintah. Bersifat kritis terhadap kebijakan mereka memang perlu dilakukan, namun diusahakan untuk tidak terlalu berlebihan serta tetap berlandaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasalnya, jika kita bertindak keterlaluan atau anarkis maka akibatnya akan terhadap diri kita sendiri bahkan dapat merugikan orang lain. Kita harus berpikir sebijak mungkin sebelum melakukan sesuatu. Tidak sembarangan apalagi sampai menyinggung banyak pihak.
Selain itu, nilai-nilai ihsan lain yang dapat dipahami ialah dalam berperilaku terhadap sesama umat beragama. Hal ini sebenarnya sangat sederhana namun seringkali kita tidak hiarukan. Misalnya budaya salam-salaman ketika usai sholat berjamaah. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa hukum dari bersalaman tersebut. Apakah itu merupakan kesunahan atau hanya sebatas budaya. Dari berbagai kitab terkait, tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa bersalaman usai sholat adalah hal yang disunnahkan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa ini hanya merupakan budaya masyarakat Indonesia terutama yang muslim. Beberapa sumber menyebutkan bahwa salam-salaman merupakan suatu nilai yang penting dalam merangkai persaudaraan antar umat.
Berdasarkan tujuannya untuk menjalin dan mempererat persaudaraan maka pengamalanya bisa saja menjadi sunnah. Hal ini dilandasi dengan dasar bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Intinya, bersalam-salaman merupakan perilaku
14 | New Normal, Kajian Multidisiplin
berbuat baik terhadap sesama. Akan tetapi, di masa pandemi seperti sekarang, kita tidak perlu bersikukuh akan melakukanya seperti saat keadaan biasa. Sebab, hal ini justru berarti kita tidak mengindahkan peraturan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya pembatasan jarak fisik. Kita boleh saja meniadakan adat tersebut tetapi tidak berarti kita menghilangkan budaya yang selama ini telah kita bangun bersama. Seperti penjelasan yang sebelumnya, semua ini dilakukan atas dasar waspada terhadap penyebaran virus yang tak terduga dan bisa saja menyebar dimanapun dan kapanpun. Jika pandemi ini sudah berakhir maka kita seperti biasa dapat kembali ke kebiasaan lama kita yakni kehidupan normal yang sewajarnya bukan penerapan kehidupan normal baru yang telah direncanakan.
Kompetensi ini juga butuh kita ketahui sebagai wawasan baru saat pandemi. Pasalnya, tidak sedikit orang yang lantas menilai kita buruk jika kita tidak melakukan sesuatu yang sudah ala kadarnya. Salah persepsi seperti menganggap orang yang tidak bersalaman usai sholat berjamaah sebagai seseorang yang tidak menghargai norma agama dalam masyarakat bisa berujung panjang. Fenomena ini dapat terjadi jika antara satu muslim dengan muslim yang lain tidak memiliki kesamaan pemahaman yang bisa berujung fatal. Padahal tidak ada i’tikad buruk yang melandasi perlakuan salah satu di antara mereka.
Akhirnya, penerapan new normal yang diberlakukan di Indonesia saat ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki kompetensi baru terhadap suatu aspek. Termasuk aspek vital dalam kehidupan beragama dan pelaksanaan syari’at yang baik. Konteks baik ini harus pula disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang berlaku di lapangan. Tidak baik jika kita memaksakan apa yang seharusnya tidak dilakukan hanya dengan alasan untuk berperilaku baik. Ihsan dalam hal ini diartikan sebagai mencari perilaku atau akhlak yang terbaik. Singkatnya, dalam bersikap setiap orang harus berlaku seproporsional mungkin dengan penyesuaian terhadap lingkungan di sekelilingnya.
Penutup
Berdasarkan penjelasan mengenai keempat pokok kompetensi umat muslim di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslim harus dapat tangguh dalam kondisi apapun baik saat normal atau saat darurat seperti saat ini. Tangguh berarti melaksanakan kehidupan sesuai standar tiga kompetensi tersebut di atas. Meneguhkan keislaman serta keimanan terhadap Allah SWT serta menerapkan Ihsan yang baik terhadap siapa saja. Kegamangan pada diri seorang muslim
New Normal, Kajian Multidisiplin | 15
ialah disebebabkan oleh dirinya sendiri yang kurang mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ia selalu dirundung perasaan was-was dan bahkan menularkan rasa was-was tersebut terhadap lingkunganya.
Pengamalan tiga kompetensi tersebut di atas dapat merubah secara signifikan kepribadian seorang muslim dalam menghadapi keadaan darurat sekalipun. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis berharap bahwasanya umat muslim dimanapun berada tetap dapat memahami dan memiliki esensi ketiga kompetensi tersebut. Sehingga, pandemi ini dapat segera berakhir dan kehidupan manusia dapat kembali ke keadaan normal seperti sedia kala. Amin.
Rujukan
[1]. https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html . 2020.
[2]. https://www.google.com/search?q=peta+sebaran+corona+di+dunia&oq=peta+sebaran+corona+di+dunia&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 2020.
[3]. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935387/who-tetapkan-virus-corona-sebagai-pandemi-ini-artinya. 2020.
[4]. Muslim, bin al- Hajjaj, Shahih Muslim, Srabaya: al-Bidayah, 2018. [5]. Abdul Wahab Khllaf, Ilmu Ushulu al-Fiqh, Daar Kutub al-
Islamiyah, 2016. [6]. Al-Qur’an al-Kariim, [7]. Abdul Aziz, Muhammad bin Ali Abdul latif, al-I’tiqaadu al-
Qoodiri, Syamilah, Ishdar 4, 2014. [8]. Abdullah Bin Salim,Mawahibu as-saniyah (Indonesia, Daar Ihya al-
Kutub al-Arabiyah, 2018. [9]. Muhammad, Khudari Bik, Tarikhu al-Tasyri’I al-Islamy, Daar
Kutub al-Islamiyah, 2018. [10]. Abdul Wahab Khllaf, Ilmu Ushulu al-Fiqh, Daar al-Kutub al-
Islamy, 2016. [11]. Abu Sulaiman ad-Daarani, at-Ta’riifi li Madzhabi ahli at-
Tashawwufi, Syamilah, Ishdar 4, 2014. [12]. Muhammad Ibnu ‘Isa, at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Syamilah,
Ishdar 4, 2014. [13]. https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-jumat-
saat-pandemi-covid-19-fFlw. 2020. [14]. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Ahmad, Musnad Ahmad
Mukharrajan , Syamilah: Ishdar 4, 2014.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 17
Bab 2
Ketahanan Keluarga Perspektif Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Akrim Lubis2
Pengantar
Upaya membangun karakter bangsa kini menjadi sebuah keniscayaan bahkan kebutuhan di tengah gelombang dan dinamika perubahan sosial, modernisasi, industrialisasi dan globalisasi yang dimotori oleh kemajuan iptek terus mengalami dinamika. Saat ini kita sudah dan sedang berada pada era revolusi industri 4.0 dengan segala implikasinya baik positif maupun negatif dibidang pola pikir, pandangan, perilaku, dan orientasi hidup. Situasi ini menuntut untuk direspon secara cerdas, termasuk pendidikan dan pembinaan karakter pada umumnya, maupun karakter yang berbasis Islam sufisme. Eksistensi pendidikan karakter berbasis sufisme ini perlu terus direfitalisasi agar selalu siap merespon perubahan dan perkembangan zaman[1].
Era revolusi industri 4.0 adalah era yang ditandai dengan kemjuan teknologi cyber dan robot (robotics) dalam kehidupan manusia. Menurut Jeff Barden di era ini terjadi lompatan perubahan dengan cakupan meliputi: Ilmu Saraf, Psikologi Kognitif, dan Teknologi Pendidikan. Di era ini menurut Moh. Djazaman manusia dan tekonologi (Cyber) harus diselaraskan untuk merumuskan solusi alternatif bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan karakter berbasis tasawuf
Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitriah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya[2]. Keluarga memiliki fungsi-fungsi yang menjaga hu-bungan antar anggota keluarga sehingga nilai-nilai dapat terjaga dan terpelihara dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu fungsi keluarga yang paling menonjol adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan.
2 Dr. Akrim Lubis, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan
18 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Perubahan pola kehidupan keluarga yang disebabkan adanya
kemudahan mengakses informasi dalam penggunaan teknologi, menimbulkan tantangan hidup yang semakin berat dalam kehidupan berkeluarga seperti adanya informasi dunia pornografi dan tindak kriminal yang mudah diakses dan dikhawatirkan dapat di tiru dan mempengaruhi perkembangan psikologis anggota keluarga[3].
Keluarga dalam kaitan pendidikan diungkapkan oleh Imam Barnadib sebagai salah satu pusat pendidikan. Bahkan disebut sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Made Pidarta mengemukan lebih jauh bahwa pendidikan keluarga sebagai pendidikan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan serta mendapat pembinaan pada keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan-pengembangan berikutnya.[4]
Pendidikan di sekolah ternyata belum mampu menjawab kege-lisahan orang tua dan masyarakat, ini terbukti masih banyak yang belum memahami agama dengan baik, baik dalam aqidah, ibadah maupun membaca Al Quran. Demikian juga banyak kasus kenakalan remaja dan siswa sekolah yang semakin merebak. Kenakalan remaja mulai dari tawuran antar siswa , narkoba, seks bebas, minuman keras, sampai kepada krisis moral, sebagai contoh adanya siswa yang mengancam atau bahkan membunuh gurunya sendiri lantaran tidak terima di ingatkan tatkala merokok.
Disinilah letak peran pendidikan keluarga, yang dapat mem-perbaiki anak mulai dari agama, akhlak, sosial dan lain sebagainya. Keberhasilan Pendidikan keluarga akan menjadi perantara bagi orang tua menuju surga dunia (rumahku surgaku) dan juga menuju surga akhirat. Adanya Anak-anak yang sholih dan sholihah, akan menjadikan kebaikan yang anak lakukan menjadi pahala yang mengalir bagi orang tua.
Belakangan ini term “ketahanan nasional” menjadi hal urgen. Hal tersebut disebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan karakter anak bangsa yang semakin jauh dari koredor adab, hukum dan agama. Salah satunya, belakangan ini melalui akun media sosial, seorang pelajar yang sedang memaki guru dengan bahasa “kotor” kemudian merekam dan disebarkan melalui media sosial. Sebelum itu juga terdapat seorang pelajar yang mengajak gurunya berkelahi. Kejadian ini sempat viral karena sikap tidak baik pelajar tersebut dan kesabaran guru yang tidak melawan perbuatan muridnya [5].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 19
Diskursus mengenai hal tersebut diatas selalu mendasari faktor utamanya adalah peran keluarga, sebab ketahanan nasional sangat ditentukan dengan ketahanan keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu-kesatuan sosial ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia [6].
Pada tulisan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana ketahanan keluarga dalam kontek pendidikan Islam dengan menghubungkannya pada era revolusi Industri 4.0 terutama pada masa pandemi saat ini.
Pembahasan
Istilah revolusi industri 4.0 sebagai sebuah proses produksi (barang) yang berlangsung secara cepat baik kuantitas maupun kualitas (hasil produksi). Istilah ini dperkenalkan pada pertengahan abad 19 oleh Friederich Engels dan Louis Auguste Blanqui. Kini telah memasuki fase keempat, dimana perkembangan dan perubahan dari fase ke fase memberi perbedaan artikulatif pada sisi kemanfaatan dan kegunaannya. Fase pertama 1.0 bertumpu pada penemuan mesin yang menitikberatkan pada mekanisasi produksi. Fase kedua 2.0 mulai beranjak pada etape produksi massal yang terintegrasi dalam quality control dan standarisasi. Fase ketiga 3.0 memasuki tahapan keseragaman secara massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase keempat 4.0 telah meng-hadirkan digitalisasi dan otomatisasi yang merupakan perpaduan internet dengan manufaktur.
Dilihat dari sejarahnya menurut Toffler perubahan yang dibawa gelombang pertama revolusi pertanian mengambil waktu ribuan tahun untuk menyelesaikan diri [7]. Gelombang kedua-kebangkitan peradaban industrial mengambil waktu 300 tahun. Sejarah sekarang - gelombang ketiga yakni peradaban informasi hanya dalam beberapa puluhan tahun saja karena didukung oleh kemajuan di bidang informasi dan robotisasi. Era ini oleh Daniel Bell menyebutnya sebagai The Post Industrial Society [8].
Menurut kamus besar bahasa Indonesia perubahan berarti hal, keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah berubah-nya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu ma-syarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi
20 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat, perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Pudjiwati Sajagyo mengutip pendapat Hirschman yang mengatakan bahwa kebosanan manusia adalah penyebab suatu perubahan[9].
Manusia sering tidak puas dan bosan pada satu keadaan dan berusaha untuk mencari cara atau alternatif lainnya untuk meng-hilangkan kebosanannya dan menemukan cara baru yang lebih menyenangkan, mudah dan murah. Bisa kita lihat pada revolusi teknologi transportasi yang demikian canggih hingga berakibat pada perubahan pola mobilitas manusia
Merujuk hasil penelitian dari McKinsey pada 2016 bahwa dampak dari digital teknology menuju revolusi industri 4.0 dalam lima (5) tahun kedepan akan ada 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau hilang dari muka bumi. Hasil penelitian ini memberikan pesan bahwa setiap diri yang masih ingin mempunyai eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan mental dan skill yang mempunyai keunggulan persaingan (competitive advantage) dari lainnya. Jalan utama mempersiapkan skill yang paling mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik (behavioral attitude), menaikan kompetensi diri dan memiliki semangat literasi. Bekal persiapan diri tersebut dapat dilalui dengan jalur pendidikan (long life education) dan konsep diri melalui pengalaman bekerjasama lintas generasi/lintas disiplin ilmu (experience is the best teacher) [10].
Adapun keuntungan dari munculnya disruptive innovation memberikan antara lain: Pertama, dimudahkannya konsumen dalam mencukupi kebutuhan. Dengan memotong biaya yang dikeluarkan, perusahaan yang menggunakan teknologi terbaru mampu menekan biaya sehingga dapat menetapkan harga jauh lebih rendah daripada perusahaan incumbent. Dengan demikian, semakin murah biaya yang dikeluarkan konsumen semakin membuat konsumen sejahtera.
Kedua, teknologi yang memudahkan. Munculnya inovasi yang baru tentu akan membawa teknologi yang baru dan canggih, setidaknya dibandingkan dengan teknologi yang telah lama ada. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi transfer teknologi menuju yang lebih modern.
Ketiga, memacu persaingan berbasis inovasi. Indonesia meru-pakan negara yang tidak dapat begitu saja makmur tanpa adanya inovasi. Dengan adanya inovasi yang mengganggu, maka perusahaan dalam industri dipaksa untuk melkakukan inovasi sehingga terus memperbaiki
New Normal, Kajian Multidisiplin | 21
layanannya. Keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Inovasi yang dilakukan akan memberikan kesempatan lapangan kerja yang baru. Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, revolusi industri 4.0 dengan disruptive innovation-nya menempatkan pendidikan Islam di persimpangan jalan. Persimpangan tersebut membawa implikasi masing-masing. Pendidikan Islam bebas memilih. Jika ia memilih persimpangan satu yakni bertahan dengan pola dan sistem lama, maka ia harus rela dan legowo bila semakin tertinggal. Sebaliknya jika ia membuka diri, mau menerima era disrupsi dengan segala konsekuensinya, maka ia akan mampu turut bersaing dengan yang lain.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya perombakan atau reformasi di dalam tubuh pendidikan Islam. Pendidikan Islam di era 4.0 perlu untuk turut mendisrupsi diri jika ingin memperkuat eksis-tensinya. Mendisrupsi diri berarti menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berorientasi pada masa depan. Muhadjir Efendy dalam pidatonya mengatakan bahwa perlu ada reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pem-belajaran yang muktakhir agar dunia pendidikan nasional dapat menye-suaikan diri dengan dinamika zaman.
Konsep pendidikan dalam Islam mengakar jauh ke inti kesadaran eksistensial manusia. Pada dasarnya, eksistensi manusia adalah seukuran pengetahuannya tentang pencipta alam semesta. Itulah kesadaran tauhid. Dalam Islam, segala sesuatu bermula dan berasal dari tauhid. Secara tauhid, Allah Swt adalah pendidik teragung. Tauhidnya disebut tauhid rububiyyah. Kata terakhir ini seakar dengan kata tarbiyah dalam bahasa Arab yang berarti pendidikan dalam bahasa Indonesia [11].
Pendidikan Islam dalam keluarga dalam konteks ini mengacu pada peran pendidikan yang dilakukan oleh Orang tua yang menjadi figur teladan terdekat terutama ibu. “Ibu adalah madrasah. Menyiap-kannya berarti menyiapkan satu bangsa”. Begitulah puisi Hafez Ibrahim yang terkenal itu. Bukan hanya madrasah, ibu adalah madrasah yang pertama dan utama. Di usia dini, anak-anak mendapatkan segalanya dari ibu: pelukan kasih sayang, contoh teladan, nilai-nilai dan kecerdasan sosial. Seluruh dimensi manusia dari fisik, jiwa, otak dan ruh dipenuhi sang ibu (tentu juga, ayah) di tahun-tahun pertama kehidupannya.
Jika bahasa yang dipakai Hafez Ibrahim adalah bahasa puisi yang mengandung makna konotatif, para pakar pendidikan memastikan
22 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang dialami oleh anak-anak. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama untuk mene-mukan dan memuaikan segala potensi anak dalam lima aspek: fisik, psikis, nalar, spiritual dan sosial. Karena begitu kompleksnya dunia anak-anak ini, Oscar Chrisman pada tahun 1893 menyebut istilah “pedology” sebagai nama ilmu yang mendalami dunia anak; ilmu yang kemudian dikembangkan oleh Jean Piagiet di Swiss, Fallon di Perancis, dan Gezel di Amerika.
Anak adalah hadiah paling berharga yang dianugerahkan Allah Swt. bagi setiap orang tua. Hadiah paling istimewa itu dibekali oleh Sang Pencipta dengan beragam kecerdasan yang belum semuanya diperla-kukan sebagaimana mestinya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga dunia. Howard Gardner menyebut 8 (delapan) kecerdasan yang built in pada makhluk indah itu: Kecerdasan linguistik, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musical, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Inilah teori kecer-dasan jamak (multiple intelligences) yang menjadi rujukan banyak ahli dan praktisi pendidikan hingga saat ini.
Membicarakan ketahanan keluarga, sesungguhnya merupakan juga membicarakan ketahanan nasional, sebab keluarga merupakan satu unsur yang menopang ketahanan nasional tersebut. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehi-dupan untuk tetap jaya diantara keteraturan dan perubahan yang terjadi. Latar belakang ketahanan nasional suatu bangsa terdiri dari kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara untuk dapat meng-hadapi perubahan lingkungan dan mempertahankan kelangsungan hidup meskipun mengalami berbagai gangguan dan ancaman.
Ketahanan nasional tidak hanya meliputi aspek militer dalam hal pertahanan dan keamaan. Namun juga meliputi segala aspek kehidupan yang multidisiplin seperti aspek geografi, penduduk, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya [3].
Dalam rangka membangun dan mensejahterakan institusi keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera [12] disebut-kan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 23
keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.
Berdasarkan amanat Undang-Undang di atas, maka sudah men-jadi suatu keharusan bagi setiap anggota keluarga wajib mengembang-kan kualitas diri dan fungsi keluarga. Pengembangan berupa sumber daya manusia (SDM) berpotensi dalam membentuk kemandirian dan mampu mengembangkan kualitas keluarga. Peningkatan SDM tersebut dapat berupa peningkatan pada sisi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, mental-spritual serta nilai-nilai keagamaan yang sangat penting untuk membentuk pola pikir dalam menyikapi sebuah persoalan. Hal ini dilandasi karena manusia merupakan makhluk sosial dan tak akan pernah bisa lepas oleh pergulatan sosial
Manusia sebagai makhluk sosial atau yang menurut Aristoteles disebut dengan Zoon Politikon, dikodratkan hidup dalam kebersamaan dalam masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan yang disebut sebagai masyarakat. Relasi tersebut menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.
Agar tercapainya pola hubungan yang bersifat timbal balik sebagaimana di atas, dapat dilakukan dengan membangun mental dan jiwa yang mapan, salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan secara secara internal dan non-formal berbasis keluarga. Jadi tidak hanya pendidikan yang diterapkan di sekolah formal. Alasannya adalah keluarga menjadi tempat paling strategis dalam membangun karakter manusia. Melalui pranata inilah anak manusia untuk pertama kalinya mengalami proses pendidikan yang sesungguhnya. Anak-anak mengenal cara berkomunikasi, berbahasa, berinteraksi dengan sesama. Hingga pada akhirnya, setiap anggota keluarga siap secara intelektual, pribadi, sosial, spiritual dan fisik [13].
Penanaman nilai-nilai atau yang lebih familiar dengan sebutan norma-norma tak ayal menjadi suatu keharusan. Tidak hanya yang bersifat duniawi semata, pendidikan agama yang diterapkan dalam keluarga tetap menjadi pondasi utama. Bahkan harus dimulai sejak usia dini. Bahkan, edukasi tersebut telah dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan. Sejumlah masyarakat modern misalnya, telah memulainya dengan menggunakan berbagai metode seperti yang marak dilansir oleh media belakangan.
24 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Seluruh anggota keluarga ditanamkan kesadaran untuk melaku-
kan pilihan antara nilai-nilai yang dikategorikan salah atau benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Kebiasan-kebiasaan itu dapat dimulai dengan mempraktekkannya dalam kegiatan sehar-hari. Kemu-dian berlanjut dengan internalisasi nilai-nilai sebagaimana di atas, hingga mendarah daging dalam kehidupan seluruh anggota keluarga [14].
Jika meminjam konsep yang ditawarkan Aristoteles, institusi keluarga pada dasarnya tentu tidak berdiri sendiri. Sejumlah paguyuban yang langgeng di tengah masyarakat turut menopang pertahanan dari institusi keluarga. Keluarga tumbuh dan berkembang dalam institusi sosial sebagai bagian dari sistem sosial keseluruhan.
Lembaga-lembaga kemasyarakatanpun turut menjadi suplemen dalam membentuk kepribadian anak bangsa, seperti (1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubung-an pemenuhan kebutuhan, (2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, (3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
Pelbagai penelitian menggambarkan bagaimana pengaruh pendi-dikan agama dalam keluarga dan sebaliknya mengenai pengaruh keluarga dalam pembentukan karakter. Anastasia misalnya dalam pene-litian tesis yang dilakukan pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan agama terhadap kedi-siplinan siswa, dan juga terdapat pengaruh yang signifikan keberadaan keluarga terhadap kedisiplinan siswa [15].
Revitalisasi Ketahanan Keluarga di Era Revolusi 4.0
Menelisik dari pengertian keluarga dan ketahanan nasional dapat dikorelasikan satu dengan lainnya. Diantaranya adalah usaha untuk mewujudkan ketahanan nasional haruslah didasari dari lembaga masyarakat paling kecil yaitu keluarga. Telah disebutkan beberapa pendidikan karakter dasar dalam keluarga, jika hal ini terlebih dahulu dibentuk maka tujuan nasional dan ketahanan nasional akan terwujud dengan sendirinya, karena telah memiliki karakter yang mantap [16].
Pengertian keluarga juga dapat dilihat dari dua dimensi hu-bungan, yakni: hubungan darah dan hubungan sosial. Dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh
New Normal, Kajian Multidisiplin | 25
hubungan darah antara satu dan lainnya. Berdasarkan hubungan ini keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti.
Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walau-pun bisa saja diantara mereka tidak terdapat hubungan darah. Atas dasar dimensi hubungan sosial ini terdapat keluarga psikologis dan keluarga pedagogis. Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing saling merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempenagruhi, saling memperhatikan, dan saling
Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya merujuk kembali pada norma dasar ajaran Islam sebagai basis keilmuan pendidikan Islam. Ini artinya diperlukan serangkaian aktifitas yang menjadikan keluarga pada masyarakat untuk melakukan upaya revitalisasi. Hal ini penting untuk disadari, sebab perubahan pola dan karakteristik kehidupan keluarga merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.
Pada umumnya, Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang bermuara pada kesejahteraan dan kebahagiaan, namun yang sering terjadi adalah sebaliknya beberapa kenyataan bahwa selama dekade itu terus terjadi perubahan dalam keluarga dan perubahan yang dimaksud telah mendekati bentuk yang sebelumnya dianggap sebagai bukan keluarga. Perubahan bentuk ini beriringan dengan perubahan fungsi dan proses dalam keluarga. Tampaknya, perubahan itu akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya.
Hampir semua tokoh, pemerhati dan praktisi pendidikan menya-takan bahwa dari tiga lingkungan pendidikan atau tiga pusat pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang sangat vital dan dianggap paling berpengaruh terhadap proses dan perkem-bangan seorang anak didik. Eksistensi keluarga sebagai lingkungan pendidikan sebenarnya tidak kalah penting dengan sekolah yang selama ini dianggap sebagai episentrum pendidikan bagi anak.
Bahkan, bisa dikatakan bahwa sekolah tidak akan berhasil jika tidak ditunjang oleh keluarga yang kuat dan peduli terhadap perkem-bangan pendidikan anak. Namun, realitas di lapangan menunjukan bahwa banyak anggota masyarakat yang tidak atau belum menempatkan keluarga sebagai pusat pendidikan yang ramah bagi anak-anaknya.
26 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Akibatnya, banyak anak yang kecerdasan dan mentalnya berkem-
bang secara tidak seimbang. Bahkan, merebaknya kenakalan anak-remaja seperti geng motor, pecandu narkoba, pergaulan bebas, gaya hidup hip-hop dan lain sebagainya, merupakan efek dari tidak berfungsinya keluarga dalam memberikan edukasi kepada anggota keluarganya. Terjadinya penyimpangan perilaku anak-remaja sebagaimana dijelaskan di atas merupakan salah satu akibat yang paling nyata dari tidak maksimalnya peran orang tua dalam proses pendidikan bagi anaknya.
Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya terutama menyangkut perkembangan pendidikannya, menyebabkan dia tidak betah di dalam keluarganya sendiri, sehingga tidak jarang seorang anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar lingkungan keluarganya. Hal ini menyebabkan pergaulannya tidak terpantau dengan baik. Akibatnya, anak berada dalam lingkungan yang salah. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mengembalikan keluarga sebagai pusat pendidikan, tentu dengan tetap menjadikan sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang bisa menopang dan membantu keluarga dalam upayanya membentuk generasi unggul, bermartabat dan berakhlaq.
Selain mengenal konsep, makna dan hakikat keluarga, hal lain yang juga perlu diketahui adalah mengenai tipologi dan bentuk keluarga yang berkembang dalam masyarakat. Dalam mengurai tipologi dan bentuk keluarga ini para pemerhati ilmu-ilmu sosial juga berbeda pandangan dalam pengelompokannya. Tentu, Perbedaan-perbedaan ini tidak terlepas dari berbedanya sudut pandang yang digunakan. Keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan garis keturunan, jenis perkawinan, pemukiman, jenis anggota keluarga dan kekuasaan
Berdasarkan jenis perkawinan, keluarga dikelompokan menjadi keluarga monogami dan poligami, Monogami adalah sebuah keluarga yang seorang suami hanya mempunyai seorang istri sedangkan Poligami adalah sebuah keluarga yang mana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu istri. Tipologi keluarga juga bisa dilihat Berdasarkan Pemukiman, berdasarkan kategori pemukiman keluarga dikategorikan menjadi: Patrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga sedarah suami. Matrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga satu istri Neolokal adalah pasangan suami istri, tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 27
Menurut Resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah ”sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasi-kan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga, sejahtera”[17].
William Bennett seorang pakar pendidikan menguraikan bahwa keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejah-teraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalannya.
Tokoh lain yang mengemukan pendapat terkait dengan peran dan fungsi keluarga adalah Mohammad Isa Soelaeman, menurutnya, keluarga itu hendaknya berperan sebagai pelindung dan pendidik bagi anggota keluarganya, sebagai penghubung mereka dengan masyarakat, sebagai pencukup kebutuhan-kebutuhan ekonominya, sebagai pembina kehidupan religiusnya, sebagai penyelenggara rekreasi keluarga dan pencipta suasana yang aman dan nyaman bagi anggota keluarganya dan khususnya nagi suami istri sebagai tempat memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya[18].
Dari beberapa uraian tentang peran dan fungsi keluarga di atas dapat diperinci dan dijabarkan lagi sebagai berikut: 1. Fungsi Edukasi Fungsi; edukasi keluarga adalah fungsi yang
berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi menyangkut beberapa hal mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, penyediaan sarana prasarananya evaluasinya dan lain sebagainya.
2. Fungsi religi Keluarga mempunyai fungsi religius. Artinya, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Anak diperkenalkan, dibimbing untuk beribadah serta diminta untuk membiasakan, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan perilaku keagamaan dalam kehidupannya.
3. Fungsi ekonomi Fungsi ekonomi bertujuan agar setiap anggota keluarga dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya sebagai manusia, diantaranya kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian untuk menutup tubuhnya dan kebutuhan tempat tinggal.
28 | New Normal, Kajian Multidisiplin
4. Fungsi proteksi yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan
melindungi anggota keluarganya baik fisik, non fisik, mental, moral maupun sosialnya. Fungsi ini menjadikan keluarga sebagai tempat yang aman dari berbagai macam gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal dan keluarga bisa menjadi tembok penangkal dari segala pengaruh negatif yang masuk, baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang, di dunia maupun di akhirat
5. Fungsi sosilaisasi Fungsi sosialisasi berkaitan dengan usaha orangtua sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter-relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
6. Fungsi afeksi Ciri utama sebuah keluarga adalah adanya ikatan emosional yang kuat antara para anggotanya. Dalam keluarga terbentuk rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, rasa keseikatan dan keakraban yang menjiwai anggotanya. Fungsi afeksi dalam keluarga adalah untuk memupuk dan menciptkan kasih sayang dan cinta kasih antara sesama anggotanya.
7. Fungsi reproduksi Keluarga sebagai sebuah organisme memiliki fungsi reproduksi, dimana setiap pasangan suami-istri yang diikat dengan tali perkawinan yang sah dapat memberi ketururanan berkualitas sehingga dapat melahirkan anak sebagai keturunan yang akan mewarisi dan menjadi penerus tugas kemanusiaan.
8. Fungsi biologis Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis, kebutuhan bilogis merupakan kebutuhan yang cukup vital bagi manusia. Oleh karena itu salah satu fungsi keluarga adalah memenuhi kebutuhan biologis ini. Diantara kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya.
9. Fungsi rekreasi Fungsi rekreasi keluarga adalah fungsi untuk menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang nyaman, menyenang-kan, hangat, dan penuh gairah bagi setiap anggota keluarga untuk dapat menghilangkan rasa lelah dan letih. Keluarga juga dijadikan tempat/medan rekreasi atau tempat hiburan bagi anggota keluarga-nya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan.
10. Fungsi transformasi Fungsi transformasi berkaitan dengan peran keluarga dalam hal pewarisan tradisi dan budaya kepada generasi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 29
setelahnya. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat yang paling efektif untuk melestrasikan adat-adat atau tradisi- tradisi keluarga, terutama tradisi-tradisi yang baik dan perlu dilestarikan
Beberapa fungsi tersebut menggambarkan bahwa menjadikan keluarga sebagai lingkungan pendidikan berarti menjadikan semua aktivitas dan suasana dalam keluarga bernuansa atau mengandung nilai- nilai pendidikan. Untuk memperkuat kembali peran dan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan yang akan membangun karakter anak dalam rangka membangun karakter bangsa, maka perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan beberapa upaya re-vitalisasi dalam beberapa aspek yang salah satu diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Re-vitalisasi peran dan fungsi orang tua dalam membangun dan
mengembangkan pendidikan dalam keluarga adalah dengan mengoptimalkan dan memvitalkan kembali peran dan fungsi orang tua. Selama ini peran dan fungsi orang tua cenderung tidak berjalan dengan baik, bahkan kebanyakan orang tua tidak menempatkan dirinya sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Orang tua tidak hanya sebagai pelindung dan penanggung jawab ekonomi tapi juga penanggung jawab dalam perkembangan pendidikan anaknya. Artinya, orang tua diharapkan dapat menjadi educator, motivator dan suri tauladan bagi anaknya.
2. Re-vitalisasi suasana lingkungan keluarga artinya perlu dilakukan penyuluhan intensif dan khusus bagi para orang tua agar mendapat-kan pengetahuan bagaimana menerapkan pola dan gaya hidup yang baik dalam keluarga. Orang tua juga harus dibekali dengan ilmu mengenai wawasan dunia anak, metode mendidik anak dan lain sebagainya.
3. Re-vitalisasi hubungan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan cara membangun komunikasi intensif dengan memberikan penguatan apa yang diajarkan, dan hal positif yang sudah ditanam-kan dalam keluarga harus juga dikembangkan di sekolah, atau hal-hal positif yang sudah terbangun dalam keluarga dan di sekolah harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.
Penutup
Menjadikan keluarga yang baik dan berkualitas maka harus selalu ada upaya dan usaha untuk selalu mengoreksi dan memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan terutama pendidikan Islam. Termasuk dalam upaya perbaikan tersebut adalah memperbaiki
30 | New Normal, Kajian Multidisiplin
lingkungan pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, Ada tiga lingkungan pendidikan yang biasanya sering diuraikan dan dibahas dalam buku- buku ilmu pendidikan yakni lingkungan keluarga, sekolah dan masya-rakat. Tiga lingkungan ini biasanya dikenal dengan istilah tripusat pendidikan. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai, peran, fungsi dan karakteristiknya masing-masing, antara satu dengan yang lainnya saling berkelindan dan saling menguatkan. Salah satunya adalah diperlukan serangkaian upaya revitalisasi untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan.
Rujukan
[1] U. S. K. Usman Malik Abdul, “Revitalisasi Pendidikan Karakter Berbasis Sufiisme Merespon Era Revolusi Industri 4.0,” Shaliha, vol. 2, no. 2, pp. 96–106, 2019, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
[2] S. Romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum,” Mimb. Pendidik., vol. XXV, no. 1, pp. 67–72, 2006.
[3] L. Amalia, “Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional,” Param. J. Pendidik. Univ. Negeri Jakarta, vol. 30, no. 2, pp. 132–150, 2018, doi: 10.21009/parameter.302.05.
[4] D. Yunianto, “KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN DI TENGAH,” Ta’dibuna J. Pendidik. Islam, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2020.
[5] R. Nunung Sri, “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja,” J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl., vol. 2, no. 1, 2014.
[6] K. Qolbi, “Pendidikan Agama Islam Bagi Remaja Di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu,” J. HIKMAH J. Pendidik. Islam, vol. Vol. 7, no. No. 2.
[7] T. Alvin, Gelombang Ketiga. Jakarta: Pantja Simpat, 1990. [8] B. Daniel, The Coming of Post Industrial Society. New York: Basic
Books, 1976. [9] Syamsidar, “Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap
Pendidikan,” Al-Irsyad Al-Nafs J. Bimbing. Penyul. Islam, vol. 2, no. 1, pp. 83–92, 2015.
[10] S. Priyatmoko, “MEMPERKUAT EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA 4.0,” Ta’lim, vol. 1, no. 2, pp. 1–19, 2018.
[11] B. Mulianah, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pola Asuh Keluarga Sasak Nusa Tenggara Barat,” vol. 8, no. 1, pp.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 31
37–50, 2019. [12] “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.” [13] Mohamad Surya, Bina Keluarga. Semarang: Aneka Ilmu, 2001. [14] Herimanto dan Winarmo, Ilmu sosial & budaya dasar. Jakarta: Bumi
Aksara, 2010. [15] Anastasia Lipursari, Pengaruh Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keluarga terhadap Karakter Disiplin Siswa di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, (Tesis Program Pascasarjana Tahun 2007), tidak diterbitkan. .
[16] F. S. Nur, “REVITALISASI PARENTING LUQMAN (USAHA PROGRESIF MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL MELALUI KELUARGA),” Al-I’jaz J. Kewahyuan Islam, vol. Vol 1, no. 1, p. 66, 2019.
[17] M. Ratna, “Peran Keluarga Dalam Membangun Bangsa Berkualitas: Penghargaan Kembali Terhadap Kiprah Wanita Dalam Pengasuhan Anak,” Makalah pada Seminar Nasional Peran Dan Fungsi Wanita Perspektif Kesejahteraan Umat.
[18] Moehammad, Isa Soelaeman, Pendidikan Keluarga. Bandung: Alfabeta, 1994.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 33
Bab 3
Pandemi dalam Naskah Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn dan Naskah Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar3
Pengantar
Tahun 2020, negara Indonesia dan hampir seluruh negara-negara di dunia mengalami wabah pandemik bernama Covid-19. Patut dicatat, fenomena wabah sejatinya telah terjadi berulangkali sepanjang sejarah umat manusia. Berbagai catatan sejarah melalui literasi tulis yang ada memberi informasi tentang hal itu.[1] Bahkan, pandemi yang muncul di setiap masa senantiasa melahirkan pergolakan politik.[2]
Dalam sejarah, para dokter Muslim mendeskripsikan wabah-wabah yang terjadi dalam tinjauan medis, lalu dicarikan solusi dan penanganannya secara medis pula. Hal ini menginisiasi munculnya teknik-teknik pengobatan dan obat-obatan yang relevan untuk penyakit (wabah) tersebut. Sementara itu para fukaha dan ahli agama juga ikut memberi kontribusi dari sisi hukum dan hikmah dari wabah pandemi itu. Para fukaha dan ulama berperan menangkis pemahaman-pemahaman yang berkembang bahwa wabah tersebut merupakan konspirasi makhluk halus sehingga memerlukan terapi supranatural.
Selain itu, para ahli agama juga berperan mengedukasi masya-rakat setiap kali terjadi wabah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak taubat, istigfar, sabar, dan rida, serta menerima dan menyadari sepenuhnya semua adalah ketentuan Allah.
Khusus terhadap fenomena Tha’un (penyakit menular global), sejatinya telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah, hal ini sebagai-mana telah tercatat dalam buku-buku sejarah yang menginformasikan tentang kapan dan dimana saja wabah Tha’un itu pernah terjadi, berapa jumlah orang yang meninggal dunia disebabkan wabah itu, bagaimana respons masyarakat ketika itu, dan lain-lain. Bahkan, beberapa literatur tentang wabah adakalanya ditulis karena memang telah terjadi atau sedang terjadi ketika itu.
3 Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatra
Utara,Medan
34 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Diantara literatur klasik yang membahas tentang pandemi adalah
naskah berjudul “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” Karya Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqallany (w. 852 H/1448 M) dan naskah “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un” adalah karya al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M).
Pembahasan
Pandemi Dalam Sejarah
Pandemi (wabah, tha’un) telah terjadi sepanjang sejarah di berbagai negeri Islam dan negeri-negeri lainnya. Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M) menginformasikan bahwa wabah Tha’un pertama terjadi adalah Tha’un Syairawiyah di Mada’in pada tahun ke-6 H/12 M yaitu di zaman Nabi Saw. Lalu Tha’un ‘Amwas (nama desa antara Quds dengan Ramlah) tahun 17 H atau tahun 18 H yaitu di Syam, yang merenggut 25 ribu orang (ada yang mengatakan 30 ribu orang), dimana pada pandemi ini juga banyak menewaskan sejumlah sahabat seperti Abu Ubaidah, Mu’adz bin Jabal, Abu Malik al-‘Asy’ary, Yazid bin Abi Sufyan, al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, dan lain-lain.
Lalu Tha’un di Kufah tahun 49 H. Lalu di Hasanah tahun 53 H. Lalu di Mesir tahun 66 H. Lalu di Basrah tahun 69 H (dinamakan juga dengan Tha’un ‘al-Jarif’ yang merenggut puluhan ribu nyawa. Lalu di Mesir lagi tahun 85 H. Lalu di Basrah yaitu Tha’un ‘al-fityat’ dan ‘al-‘adzry’ tahun 87 H, dinamakan demikian oleh karena sangat banyak orang yang meninggal dunia. Lalu Tha’un ‘al-asyraf’, dinamakan demikian karena banyaknya orang-orang mulia yang wafat. Lalu Tha’un ‘Ady bin Arthah tahun 100 H. Lalu Tha’un tahun 115 H di Syam. Lalu tahun 131 H di Syam lagi. Lalu tahun 134 H di Rayy. Tahun 146 H di Bagdad. Lalu tahun 221 H dan tahun 249 H di Irak. Lalu tahun 228 H di Azerbaijan. Lalu tahun 229 H di Persia. Tahun 301 di Bagdad. Tahun 324 H di Isfahan. Tahun 346 H di Irak. Tahun 406 H di Basrah. Tahun 423 H di India. Tahun 425 H di Syiraz, yang mewabah hingga ke Basrah dan Bagdad. Tahun 439 H di Mousil, Jazirah Arab, dan Bagdad. Tahun 449 H di al-‘ajm. Di Mesir tahun 455 H. Tahun 499 H di Damaskus. Tahun 478 H di Irak. Tahun 556 H di Hijaz dan Yaman. Tahun 575 H di Bagdad. Tahun 630 H di Mesir.
Lalu tahun 749 H. Tahun 781 H, 791 H, 821 H, 833 H, 841 H di Mesir. Tahun 847 H (di bulan Zulhijah) sampai Rabiul Awal tahun 848 H.Lalu tahun 853 H, 864 H (di Mesir dan Syam). Tahun 873 H, 881 H. Tahun 896 H di Romawi. Tahun 897 H di Aleppo, dan seterusnya.[3][4]
New Normal, Kajian Multidisiplin | 35
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn”Karya Ibn Hajar al-‘Asqallany (852 H/1448 M)
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” karya Ibn Hajar al-‘Asqallany (w. 852 H/1448 M) ini berisi dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berisi sejumlah fasal pembahasan.[5]
Bab pertama: Tentang mabda’ Tha’un. Ada 4 fasal: (1) penjelasan bahwasanya ia menular di kalangan orang-orang dahulu, (2) penjelasan bahwa wabah itu rahmat bagi umat Nabi Muhammad Saw, (3) penjelasan tentang orang-orang yang tertular di zaman dahulu, dan (4) penjelasan apa-apa yang rumit tentangnya.
Bab kedua: tentang terminologi. Ada 9 fasal: (1) tentang asal-usul kata Tha’un, (2) penjelasan bahwa Tha’un lebih spesifik dari wabah, (3) hadis-hadis terkait dan penjelasan bahwa ia merupakan kejahatan Jin, (4) tentang jawaban atas problematika yang muncul, (5) tentang tata cara mengkompromikan antara statemen “ikhwanikum” dan “a’da’ikum”, (6) penjelasan bahwa Jin menguasai dan memaksa manusia, (7) hikmah tentang penguasaan Jin, (8) tetang doa-doa (zikir) yang akan menjaganya dari tipu daya Jin, lalu penjelasan dari ayat-ayat al-Qur’an, dan doa-doa Nabi saw. (9) penjelasan hal-hal rumit dalam bab ini.
Bab ketiga: penjelasan bahwa Tha’un itu ‘syahadah’ bagi umat Muslim. Ada 10 fasal: (1) hadis-hadis terkait, (2) dalil bahwa syahadah diperoleh dengan niat, (3) makna syahid, (4) tentang jawaban siapaun yang berdoa dengan syahadah bersamaan memperdayakan orang-orang kafir, dan harapan maksiat akan terhalang. (5) tentang dalil tingkatan dan keutamaan para syahid. (6) tentang bahwa syahid di medan perang lebih utama dari semua syahid tanpa terbunuh kecuali Tha’un, maka ia terhitung syahid juga. (7) tentang syarat-syarat dikategorikan syahid dalam wabah Tha’un dibandingkan dengan syahid di medan perang. (8) tentang jawaban doa Nabi Saw untuk kota Madinah yang tidak dimasuki Tha’un. (9) tentang jawaban atas hadis kondisi Tha’un sebagai rahmat atau syahadah, dan penjelasan tentang kebanyakan sebab-sebab terjadinya Tha’un.(1) penjelasan tentang apa-apa yang rumit pada bab ini.
Bab keempat: hukum suatu negeri yang terjadi Tha’un. Ada 4 fasal: (1) penahanan keluar dari suatu daerah dengan melarikan diri. (2) tentang kisah Umar bin Khattab tatkala pulang dari perjalanan ke Syam dimana di Syam terjadi Tha’un, informasi tentang Abdurrahman bin Auf tentang hal itu, perbedaan para sahabat tentang hal itu dan ulama sesudah mereka, penjelasan (hukum) orang yang keluar dengan
36 | New Normal, Kajian Multidisiplin
melarikan diri (meninggalkan desa) atau berniat melarikan diri dan bantahan atasnya, dan kombinasi dua hadis terkait. (3) penjelasan tentang hikmah terhadap larangan keluar dari suatu negeri yang terjadi Tha’un. (4) penjelasan apa-apa yang problematik dalam bab ini.
Bab kelima: tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap Tha’un tatkala telah mewabah. Ada 5 fasal: (1) adakah dianjurkan berdoa agar wabah itu hilang atau tidak? Jika dianjurkan, adakah dianjurkan berkumpul jika telah mewabah secara umum? Jika tidak dianjurkan, adakah mencukupi kunut nazilah? Ataukan dikiyaskan dengan kunut nazilah yang dianjurkan berpuasa sebelumnya? Lalu adakah dianjurkan keluar ke lapangan seperti halnya salat istisqa’? (2) jika Tha’un telah mewabah secara umum harus ditakuti ataukah tidak? (3) tentang berhati-hati pada saat terjadi Tha’un dan penyakit-penyakit lainnya, lalu pembahasan tentang penyenbuhan dan obat-obatan. (4) adab (etika) terhadap orang yang tertimpa musibah Tha’un, yaitu berdoa kepada Allah memohon kesehatan, bersabar, rida, dan berbaik sangka kepada Allah. Lalu adab tatkala berobat dan keutamaannya, dan lain-lain. (5) penjelasan tentang apa-apa yang problmatis pada bab ini.
Adapun bagian akhir buku (khatimah), berisi informasi tentang pandemik Tha’un yang pernah terjadi dalam Islam, dan sekilas tentangnya.
Jika diringkas, secara umum buku ini membahas 3 hal, yaitu: pertama, tentang penyakit Tha’un. Kedua, tentang obat-obatan. Ketiga, tentang kepustakaan penyakit Tha’un. Di bab pertama Ibn Hajar menjelaskan tentang awal-mula, dimana menurutnya Tha’un itu adalah sejenis penyakit (pandemik) yang menular di tengah masyarakat silam. Selain itu, Ibn Hajar menjelaskan bahwa Tha’un itu sejatinya adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, bersabar, dan rida. Adapun latar belakang Ibn Hajar menulis buku ini diantaranya adalah karena banyaknya pertanyaan dan permintaan dari kolega-koleganya untuk mengumpulkan informasi seputar pandemi Tha’un, yaitu dengan memberi penjelasan atasnya, dan mempermudah makna dan pemahaman atasnya, serta aturan (hukum) atasnya. Maka dengan gembira Ibn Hajar menerima permintaan itu.[5]Latar belakang semacam ini adalah hal lumrah terjadi di zaman silam.
Namun seperti dijelaskan Ahmad ‘Isham ‘Abd al-Qadir al-Katib (pentahkik“Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn”), penulisan buku ini sempat terhenti beberapa waktu dan baru selesai tahun 833 H.[6]Adapun salinan naskah yang digunakan pentahkik dalam buku ini ada 4 salinan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 37
naskah yang tersebar di berbagai tempat, yaitu: 1) perpustakaan al-Auqaf asy-Syarfiyah, Aleppo; 2) naskah Perpustkaan Dar al-Kutub azh-Zhahiriyah, Damaskus; 3) naskah Perpustakaan Hagia Shopia, Sulaimaniyah, Istanbul, dan 4) naskah Perpustakaan al-‘Utsmaniyah, Aleppo.
Berikut adalah beberapa salinan lembar naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” karya al-Hafizh Ahmad bi Ali bin Hajar al-‘Asqallany (w. 852 H/1448 M) yang bersumber dari “Maktabah al-Ustadz ad-Duktur Muhammad bin Turky at-Turky” (yang sumber aslinya berasal dari Perpustakaan Escurial, Spanyol, nomor 443). Salinan lengkap naskah ini dapat diunduh di: https://www.alukah.net/library/0/128309/ (unduh terakhir 31 Maret 2020 jam 17:04 WIB).
Lembar judu
Naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” Naskah “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un” karya Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M)
Naskah “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un”ini telah ditahqiq oleh Dr. Muhammad Ali al-Bar, diterbitkan oleh Dar al-Qalam (Damaskus), terdiri dari 295 halaman. Adapun kajian (dirasah) pentahkik buku ini secara umum adalah sebagai berikut: 1. Sekilas sejarah tentang pandemik Tha’un. Disini dijelaskan sejarah
wabah Tha’un di dunia dan wabah-wabah Tha’un yang pernah terjadi sebelumnya di kalangan Bani Israil.
2. Sebab-sebab terjadinya Tha’un menurut medis dan hadis-hadis Nabi Saw. Muhaqqiq mengkomparasi sebab-sebab terjadinya Tha’un di
38 | New Normal, Kajian Multidisiplin
kalangan orang-orang dahulu (qudama’). Muhaqqiq juga menjelas-kan apa-apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Saw tentang kejahatan Jin, dan lain-lain.
3. Gejala wabah Tha’un dalam khazanah klasik (turats), medis, dan hadis. Disini juga dijelaskan secara detail tentang keunikan (i’jaz) dan keagungan hadis-hadis Nabi Saw terkait pandemik Tha’un. Juga dijelaskan apa-apa yang telah ditulis para fukaha dan ahli hadis tentang ini, serta urgensi kecermatan analisis para dokter di zaman itu.
4. Tentang karantina pandemik Tha’un. 5. Catatan-catatan dan karya-karya tentang Tha’un dan wabah dalam
turats Islam. 6. Naskah-naskah manuskrip “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-
Tha'un”, lokasi berada, urgensi, dan keistimewaan buku ini. 7. Biografi al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy.
Adapun salinan-salinan naskah (manuskrip) “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un”diantaranya tersimpan di Dir Escurial, lalu di “Perpustakaan al-Malik ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz nomor 4685 Arab Saudi, dan lain-lain.
Suatu hari, As-Suyuthy pernah ditanya tentang sebab-sebab terjadinya wabah. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk syair, maka As-Suyuthy dalam karyanya “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un” juga menjawab dengan syair pula.[7] Berikut salinan naskahnya,
Penggalan naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn” karya al-
Imam Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 911 H/1505 M). Sumber: Perpustakaan al-Malik ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz nomor 4685 Arab
Saudi.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 39
Berikut adalah beberapa lembar naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī
Akhbār ath-Thā'ūn” yang bersumber dari “Maktabah al-Ustadz ad-Duktur Muhammad bin Turky at-Turky” (yang naskah aslinya berasal dari “Maktabah al-Baladiyah, Iskandariah, Mesir). Naskah ini dapat diunduh di: https://www.alukah.net/library/0/125926/ (unduh terakhir 31 Maret 2020 jam 17:30 WIB).
Lembar awal naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn”
Lembar ke-18 (terakhir) naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-
Thā'ūn”
40 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Buku “Ma Rawahu al-Wa'un fi Akhbar ath-Tha'un”ini secara umum
menguraikan tentang sejarah penyakit Tha’un (sejenis penyakit menular) yang banyak menimpa kaum Bani Israil dan negeri-negeri Arab-Islam beserta sebab-sebab terjadinya menurut tinjauan hadis dan medis. Dalam buku ini juga diterakan historiografi perkembangan penyakit Tha’un dari masa ke masa. Buku ini juyga memberi pesan bahwa penyakit Tha’un dapat menimpa siapa saja, sesuai dikehendaki Allah.
Adapun substansi buku ini dapat dikemuakan secara singkat sebagai berikut. Bagian pertama adalah mukadimah (pengantar) yang berisi latar belekang ditulisnya buku ini. Dimana buku ini merupakan semacam repetisi atas buku “Badzl al-Ma’un” karya Ibn Hajar al-Asqallany. Lalu bab pertama tentang hadis-hadis dan histori Tha’un.
Bab kedua, tentang hakikat dan terminologi Tha’un. Di bagian ini As-Suyuthy banyak mengutip riwayat-riwayat (hadis) dan pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Beberapa tokoh yang dikutip antara lain An-Nawawi melalui karyanya “Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat”, lalu Ibn al-Atsir, lalu Al-Hafizh Ibn Hajar, lalu Ibn al-Qayyim, dan tokoh-tokoh lainnya. Di bab ini juga dijelaskan tentang perbedaan antara wabah dengan Tha’un. Menurutnya, dengan mengutip Ibn Hajar, As-Suyuthy mengatakan bahwa Tha’un lebih spesifik wabah. Wabah adalah penyakit (pandemik) yang bersifat umum yang adakalanya dalam bentuk pandemik Tha’un dan adakalanya bukan Tha’un. Setiap Tha’un adalah wabah, namun tidak semua wabah itu Tha’un.
Di bab ini juga dijelaskan sebab-sebab terjadinya Tha’un, diantaranya dengan mengutip riwayat dari Ibn Umar, As-Suyuthy menjelaskan bahwa sebab Tha’un adalah karena merebaknya maksiat secara terang-terangan. As-Suyuthy menukil riwayat (hadis) Ibn Majah dan Al-Hakim sebagai berikut,
“Tidaklah muncul kemaksiatan di suatu kaum sehingga
dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka Tha’un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya” (HR. Ibn Majah dan Al-Hakim).
As-Suyuthy juga mengutip riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa Tha'un merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menjadikan rahmat kepada orang-orang beriman.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 41
“Dari Aisyah ra, ia bertanya kepada Nabi Saw tentang tha’un? Maka Nabi Saw menceritakan kepadanya, “Sesungguhnya tha’un itu siksaan yang dikirim Allah kepada yang siapa yang Ia kehendaki. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak seorangpun yang terkena tha’un, lalu ia tetap tinggal di negerinya dengan bersabar, dan dia yakin bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali yang telah Allah tuliskan baginya, maka ia akan mendapatkan ganjaran mati syahid“ (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i, Ahamda).
Di bab ini juga dijelaskan bahwa manakala seseorang berada di suatu negeri (desa/kota) maka tidak diperbolehkan keluar, demikian sebaliknya.[7]Lalu dikemukakan juga silang pendapat tentang pembacaan kunut nazilah saat terjadi wabah dan atau Tha’un.
Di bab ini juga terdapata fasal tentang anjuran agar segera bertaubat atas segenap dosa dan kesalahan manakala terjadi Tha’un.[7] Lalu anjuran berobat dan berhati-hatai tatkala ada wabah.
Pada bab ketiga, As-Suyuthy menjelaskan tentang kehilangan anak (keluarga) akibat wabah atau Tha’un.Di bagian ini As-Suyuthy menjelaskan betapap pentungnya sikap sabar manakala seseorang atau sekelompok orang ditimpa wabah. Juga dijelaskan balasan bagi orang-orang yang sabar terhadap musibah ini. As-Suyuthy mengutip hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa disediakan balasan berupa Surga dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bersabar manakala orang-orang yang dicintai dicabut nyawanya oleh Allah.
“Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali syurga” (HR. Al-Bukhary).
Hikmah (pelajaran) dari hadis ini diantaranya adalah bahwa Allah kadang menguji hamba-Nya dengan kematian orang-orang yang dicintainya di dunia, seperti anak dan istri serta kerabat-kerabat dekatnya. Jika dia sabar dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik di dunia dan dengan surga.
As-Suyuthy juga menjelaskan pentingnya bersyukur dan berserah diri kepada Allah (istirja’) saat tertimpa mushibah. Untuk hal ini As-Suyuthy mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ary,
42 | New Normal, Kajian Multidisiplin
“Dari Abu Musa al-Asy’ary ra,sesungguhnya Rasulullah
Saw pernah bersabda, “apabila anak seorang hamba (yang beriman) mati, Allah berfirman kepada para Malaikat-Nya, “kalian telah menggenggam anak hambaku”, maka merekapun menjawab, “ya”, dan Allah berfirman, “kalian telah menggenggam buah hatinya”, lalu mereka menjawab, “ya”, dan Allah berfirman, “apakah yang dikatakan hambaku ini?”, mereka menjawab, dia memujimu dan beristirja'”, maka Allah berfirman, “bangunkanlah untuk hambaku rumah disurga dan namakan ia dengan rumah al-hamd”.[7]
Beberapa Hikmah dan Wawasan
Melalui gambaran sebagaimana tertara dalam naskah “Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn” Karya Ibn Hajar al-‘Asqallany (w. 1448 M) dan Naskah “Mā Rawāhu al-Wā'ūn fī Akhbār ath-Thā'ūn” Karya Jalal ad-Din as-Suyuthy (w. 1505 M) yang membicarakan tentang wabah-pandemik yang telah dikemukakan sebelumnya, sejatinya ada banyak hikmah, pesan, dan wawasan yang dapat diambil. Terlebih lagi di saat momen wabah Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan masyarakat dunia saat ini. Pandemi Sebagai Sejarah Berulang
Sejatinya, pandemi telah terjadi sejak zaman Nabi Saw. Bahkan dalam catatan sejarah wabah Pandemi terjadi di seluruh dunia dan menewaskan ribuan orang. Misalnya seperti diinformasikan Ibn Hajar al-Asqallany, dalam kurun 9 bulan wabah pernah memakan korban hingga mencapai 1000 orang perhari di Damaskus.
Secara historis, wabah Pandemi sejatinya telah menjadi memori kolektif masyarakat. Hal ini tentu menjadi pengingat yang baik dan oleh karena itu menjadi cara guna mengantisipasi pandemi manakala telah mulai muncul. Berikutnya adalah mencari solusi dari wabah itu.
Dalam literatur-literatur Islam klasik juga dikemukakan bagaimana menyikapi Pandemi manakala terjadi. Diantaranya secara umum diajarkan untuk tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, seperti bersikap pasrah (pesimis). Oleh karena itu dianjurkan senantiasa berupaya (ihtiar) untuk menghindari wabah tersebut. Seperti dikemukakan dalam khazanah-khazanah (naskah-naskah) Arab klasik, cara-cara pencegahan dan atau pengobatan itu lazimnya seperti dilakukan seperti hari ini, seperti minum dan makan bergizi, pola hidup sehat, olah raga, dan lain-lain. Namun jika akhirnya Pandemi terjadi, maka hendaklah bersabar, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 43
Selanjutnya tetap mengupayakan berobat, mengikuti anjran dokter, menaati pemerintah, dan seterusnya. Poin-poin ini setidaknya telah tertera dalam naskah-naskah klasik karya ulama dan ilmuwan Muslim, dan telah dipraktikkan pula oleh masyarakat waktu itu.[8]
Isolasi dan Karantina
Sebuah hadis Nabi Saw menyatakan, “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR. Al-Bukhari). Sabda Nabi Saw ini secara implisit mengindikasikan apa yang hari ini dikenal dengan isolasi dan karantina, atau bahkan lockdown. Sejatinya, sejak jauh hari Nabi Saw telah merumuskan satu sistem penanganan penyakit menular yang kini dikenal sebagai karantina atau isolasi ini. Arti penting karantina dan atau isolasi diri adalah untuk menangkal penyebaran virus. Lebih dari itu, karantina dilakukan bukan semata bagi orang-orang yang terindikasi wabah (virus menular), namun juga bagi orang-orang yang berada di kawasan Pandemi yang memiliki kontak langsung dengan orang yang menderita wabah (virus).
Lalu, mengapa orang-orang yang tidak memiliki gejala namun berada di kawasan Pandemi perlu di karantina? Hal ini adalah karena ia berpotensi tertular dan dapat menulari orang di sekitarnya. Oleh karena itu, karantina adalah upaya pencegahan terhadap diri sendiri dan orang lain, dan pada saat yang sama memutus penyebaran wabah secara sosial-kolektif.
Sejatinya, praktik karantina telah dipraktikkan di zaman Khalifah Umar ra. Tepat pada tahun 17 H, Khalifah Umar dan rombongan melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam (Syria). Saat dalam perjalanan, rombongan bermalam di sebuah desa. Lantas Khalifah Umar diberi kabar bahwa di Syam sedang terjadi wabah penyakit menular. Spontan hal ini membuat sang khalifah membatalkan agenda perjalanan Syam dan memilih untuk kembali ke Madinah.
Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin ‘Abd Allah al-Baghdady (w. 471 H/1078 M) dalam karyanya yang berjudul “ar-Risālah al-Mughniyah fī as-Sukūt wa Luzūm al-Buyūt” membahas tentang keutamaan tinggal dan berdiam diri di rumah. Seperti diketahui, dalam situasi pandemi atau wabah, salah satu cara menghindari penularan penyakit dari satu orang kepada orang lain adalah dengan berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas di luar rumah (social psycology dan atau lockdown).
44 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Fungsi menetap di rumah ini juga adalah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus penyakit.
Hal ini sesuai hadis Nabi Saw yang menegaskan arti penting menjaga lisan dari ucapan dan ungkapan yang tidak baik, mengerjakan aktivitas yang produktif dan bermanfaat di rumah (kediaman), dan merenungi dosa dan kesalahan diri yang pernah dilakukan. Nabi bersabda, “Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, “Aku pernah bertanya pada Rasulullah saw, “apa itu sebab keselamatan?” Nabi saw bersabda, “(Keselamatan itu) yaitu hendaklah engkau menahan lisanmu, sibukkanlah rumahmu dengan ibadah kepada Allah, dan tangisilah dosa-dosamu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad).[9]
Pentingnya Menjaga Lingkungan dan Social Distancing
Seperti diketahui, diantara faktor pemicu munculnya Tha’un (wabah-pandemik) dan penyebarannya yang begitu cepat diantaranya adalah tercemarnya udara dan lingkungan, khususnya di lokasi pertama kali muncul. Dan seperti diketahui, penanganannya adalah dengan memperbaiki gizi, suhu tubuh yang stabil (tidak demam), menyeimbangkan udara dan ruangan dengan pendingin dan parfum ruangan. Lalu menjauhi tempat wabah (penyakit), demikian lagi menjauhi orang yang telah wafat karena wabah dan orang yang masih sakit, baik pakaiannya, kenderaannya, tempat tinggalnya, atau tetangganya yang terjangkit, namun jika terpaksa maka harus menahan nafas. Lalu menahan menghirup udara dan mengambil angin kencang, dan lainnya.
Tidak diragukan lagi, sumber lingkungan terpenting yang sangat diperlukan manusia adalah udara dan air. Maka jika dua hal ini rusak (tercemar) maka akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Pesan-pesan ini setidaknya telah dikemukakan Muhammad bin Ahmad at-Tamimy al-Maqdisy (hidup di abad ke-4 H/10 M) dalam karyanya yang berjudul “Maddah al-Baqa’ fi Ishlah Fasad al-Hawa’ wa at-Taharruz Min Dharar al-Auba’”.Karena itu, menjaga jarang (social distancing) penting guna menahan persebaran virus, dimana hal ini mutlak diperlukan dan seyogianya dipatuhi.[10]
Anjuran Berobat dan Menjaga Kesehatan
Islam adalah agama yang memberi perhatian besar terhadap masalah kesehatan. Hal ini tidak lain bagian dari upaya menyeim-bangkan dengan kebutuhan dan keadaan rohani. Nabi Saw pernah bersab, “Sungguh, badanmu memiliki hak atas dirimu” (HR. Muslim).
New Normal, Kajian Multidisiplin | 45
Diantara hak badan (tubuh) manusia adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman pada saat haus, memberikan istirahat pada saat lelah, membersihkan pada saat kotor dan mengobati pada saat sakit. Hal ini selain meruapakn kebutuhan tubuh, namun juga meruapakan sesuatu yang bersifat natural, dibutuhkan setiap manusia.
Bahkan, pemeliharaan kesehatan menjadi bagian pemeliharaan kedua dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok dalam syariat Islam atau yang dikenal dengan “maqashid asy-syari’ah” (tujuan pensyriatan sebuah hukum). Sebaliknya, Islam melarang berbagai tindakan yang membaha-yakan fisik dan jiwa, dimana hal ini sangat dilarang di dalam Islam. Hal ini sesuai firman Allah, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan” (QS. Al-Baqarah [02] ayat 195). Kerusakan dalam konteks ayat ini tentunya sangat umum yang mencakup segala hal yang dapat merusak dan merugikan manusia secra fisik, sosial, politik, dan lain-lain.
Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan pentingnya berobat, yaitu berupaya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya dengan keyakinan bahwa semua penyakit pasti ada obat dan penang-kalnya. Lebih dari itu lagi, penyakit juga merupakan kadar (ketentuan) dari Allah, maka upaya mencari kesembuhan dan obat pun juga merupakan bagian dari kadar Allah.[3] Sikap dan cara merespons yang seperti ini seyogianya dimiliki oleh setiap manusia (terutama insan Muslim), dengan demikian ia akan mampu menghadapai segenap cobaan dan tantangan dalam bentuk apapun, terutama cobaan pandemi (wabah/penyakit menular) Covid-19 seperti yang sedang terjadi saat ini di Indonesia dan dunia hari ini.
Penutup
Dari uraian di atas, dapat dipahami dan sekaligus ditarik sejumlah kesimpulan bahwa pandemi (wabah penyakit menular yang) yang bersifat masif dan kolektif sejatinya merupakan fakta sejarah yang selalu berulang, batapapun periode terjadi, waktu, dan tempatnya tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dalam kenyataannya, wabah kolektif (pandemi) Covid-19 ini telah meluluh lantakkan hampir semua sendi kehidupan manusia, dimana dampak yang paling dominan dan dapat dirasakan adalah bidang pendidikan dan perekonomian. Namun demi-kian, dibalik pandemi tersebut ternyata ada sejumlah hikmah dan pesan yang dapat dipetik dan lalu diamalkan dalam kehidupan.
Melalui review dan analisis singkat dua naskah klasik yang ditulis oleh ulama silam di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi sejatinya merupakan sebagai sejarah yang berulang. Lalu manakala wabah
46 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pandemi itu terjadi, para ulama dan dokter menganjurkan untuk melakukan isolasi dan karantina baik secara mandiri maupun secara struktur. Berikutnya dengan wabah pandemi ini juga menegaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat dimana pribadi, keluarga, dan masyarakat berada. Sedangkan puncak spiritual dari terjadinya pandemi adalah dianjurkannya kepada insan Muslim untuk berobat memohon ampun atas segenap salah dan ketelodran yang telah merebak dan merajalela di muka Bumi. Dengan cara dan sikap seperti ini maka kita akan tetap dapat mengambil hikmah, pesan, dan kearifan dari segenap peristiwa yang terjadi. Wallahu a’lam
Rujukan
[1] A. M. R. Maulana, “Pandemi Dalam Worldview Islam Dari Konsepsi ke Konspirasi,” J. TRIBAKTI, vol. 31, no. 3, pp. 312–315, 2020.
[2] Rusdi, “Pandemi Penyakit Dalam Lintasan Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik,” J. Diakronika, vol. 20, no. 1, p. 51, 2020.
[3] A. J. R. Butar-Butar, Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam. Medan: UMSU Press, 2020.
[4] M. bin A. bin Al-Khathib, Muqni’ah as-Sā’il ‘an al-Maradh al-Hā’il, Tahkik: Hayyah Qarah. Rabat: Dar al-Aman, 2015.
[5] A. bin A. bin H. Al-‘Asqallany, Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn, Tahkik: Ahmad ‘Isham ‘Abd al-Qadir Katib. Riyadh: Dar al-‘Ashimah.
[6] A. ‘Isham ‘Abd al-Q. Katib, tahkik Badzl al-Mā’un fī Fadhl ath-Thā’ūn. Riyadh: Dar al-‘Ashimah.
[7] al-H. J. ad-D. As-Suyuthy, Ma Rawahu al-Wa’un fi Akhbar ath-Tha’un. Iskandariah: Maktabah al-Baladiyah.
[8] R. ‘Abd Ar-Rahim, Risalah an-Naba ‘an al-Waba li Zain ad-Din bin al-Wardy . Dirasah Naqdiyah. Jami’ah an-Najah li al-Abhats al-‘Ulum al-Insaniyah. 2010.
[9] D. Badri Khaeruman, Pandemi Covid-19 dan Kondisi Darurat : Kajian Hadis Tematik (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). URL: http://digilib.uinsgd.ac.id/30777/.
[10] R. H. Hidayat, “Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia,” JurnalPendidikanKesehatan, vol. 9, no. 1, p. 49, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 47
Bab 4
Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Organisasi Islam di Indonesia Rizka Harfiani4
Pengantar
Organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization), menetapkan Coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan Covid-19 sebagai pandemi [1]. Lebih dari 200 negara terdampak virus corona, termasuk Indonesia, yang penyebarannya semakin hari semakin meningkat [2]. Gejala umum terinfeksi Covid-19 adalah demam, batuk, sulit bernafas, dan adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Transmisi penularannya dari manusia ke manusia [3]. Berbagai dampak timbul akibat hadirnya virus ini, bukan hanya mengancam pada kesehatan fisik saja, tetapi juga pada kesehatan mental, khususnya para petugas medis yang berada di garda terdepan. Selain kesehatan, Covid-19 juga mengguncang perekonomian negara, merubah tatanan pola pendidikan, budaya kerja, peribadatan, sosial, ketahanan pangan, dan aspek lainnya.
Dampak kesehatan fisik dan mental sangat dirasakan oleh penderita yang terinfeksi virus corona, dan juga dirasakan oleh petugas kesehatan yang memiliki resiko kerja yang tinggi. Beberapa faktor yang teridentifikasi penyebab penularan virus, yaitu kebersihan tangan yang tidak memadai sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, penggunaan APD yang tidak tepat, anggota keluarga yang terdiagnosis, kontak dengan pasien lebih dari 12 kali sehari, jam kontak harian yang panjang (lebih dari 15 jam), dan sebagainya. Gejala umum yang dirasakan oleh petugas kesehatan dapat diidentifikasi seperti, demam, batuk, kelelahan, penggunaaan APD yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan pada kulit, serta pernafasan. Hal tersebut membuat petugas kesehatan mengalami depresi, kecemasan, insomnia, dan kesusahan [4]. Stress dan kecemasan adalah reaksi terhadap situasi yang mengancam dan tidak terduga, seperti halnya wabah Covid-19 ini [5]. Pandemi Covid-19 adalah tantangan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendukung kesehatan mental petugas medis dan petugas kesehatan
4 Dr. Rizka Harfiani, Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Medan
48 | New Normal, Kajian Multidisiplin
yang berafiliasi staf merupakan bagian penting dari respon kesehatan masyarakat [6].
Dampak perekonomian yang terjadi di Indonesia akibat Covid-19, yaitu sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya bagi yang tidak memiliki penghasilan tetap [7]. Banyak sektor yang terdampak Covid-19, seperti transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan sektor lainnya, namun sektor ekonomi yang paling terkena dampak Covid-19 adalah sektor rumah tangga [8]. Dampak sosial, secara negatif yang terjadi akibat Covid-19 adalah banyaknya pengangguran yang menjadi warga miskin baru. Sedangkan dampak positifnya adalah tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk saling tolong menolong, sehingga tercipta solidaritas sosial di masyarakat [9].
Dampak Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia adalah penutupan sementara lembaga pendidikan, yang menyebabkan terganggunya proses kegiatan belajar. Langkah ini diambil sebagai upaya menahan penyebaran virus corona, namun memberikan dampak psikologis bagi siswa dan menurunkan kualitas keterampilan siswa. Permasalahan ini merupakan tanggungjawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dalam memberikan fasilitas bagi semua stakeholder pendidikan agar kegiatan sekolah tetap berlangsung dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh [10]. Sistem pendidikan baru yang dibangun akibat dampak Covid-19, memerlukan kesiapan dan motivasi guru untuk memajukan pengetahuan dan keterampilan, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peluang untuk memajukan kualitas pembelajaran online, membutuhkan dukungan dari guru, orangtua, dan keluarga [11]. Implementasi pembelajaran daring di sekolah dapat terlaksana, apabila ada kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orangtua dalam belajar di rumah [12].
Dampak Covid-19 lainnya adalah mengubah metode dan budaya kerja. Munculnya fenomena bekerja dari rumah sebagai upaya penyebaran virus corona berdampak pada penurunan produktivitas karyawan. Fakta menemukan bahwa bekerja dari rumah tidak dapat di terima secara umum, banyak bidang pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di rumah [13]. Selain belajar dan bekerja dari rumah, beribadahpun dilakukan hanya di rumah. Salah satu dampak Covid-19 adalah penutupan sementara tempat ibadah. Padahal peran agama dimungkinkan sangat membantu dalam mengatasi kesehatan mental, seperti gejala depresi dan kecemasan, akibat pandemi Covid-19 [14].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 49
Seorang muslim percaya bahwa Islam berurusan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah psikologis, serta bagaimana muslim mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 [15]. Strategi yang dianjurkan beberapa agama bagi para jama’ahnya adalah praktek jarak jauh (social distancing), serta pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak orang [16].
Berbagai upaya dan kebijakan terkait penanganan virus ini telah dilakukan oleh Pemerintah, mulai tingkat Pusat hingga ke Daerah. Kebijakan tersebut seperti, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), melakukan karantina kesehatan dan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Semua aktifitas seperti bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan di rumah. Warga juga wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker/faceshield, pembiasaan untuk sering mencuci tangan, jaga jarak (social distancing), dan pemeriksaan suhu badan. Optimalisasi upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 merupakan bentuk pemenuhan hak warga Negara, antara lain menumbuhkan kesatuan kolektif, menciptakan stabilitas ekonomi negara, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyempurnakan kemerdekaan Indonesia [17].
Selain kebijakan dari Pemerintah, banyak organisasi Islam di Indonesia yang tidak tinggal diam dalam menanggulangi Covid-19. Bahkan organisasi tersebut bergabung untuk memperkuat imbauan Pemerintah. Contohnya saja Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), yang terdiri dari 14 ormas Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Persatuan Islam, Al-Ittihadiyah, Al-Washliyah, Az-Zikra, Syarikat Islam Indonesia, Mathlaul Anwar, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, HBMI, Persatuan Umat Islam (PUI), dan Nahdlatul Wathan. LPOI mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudik lebaran di saat kondisi Covid-19. Selain itu LPOI juga mengimbau untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tidak melakukan aktivitas buka puasa bersama, serta tidak melakukan kegiatan takbir keliling [18], sebagaimana tradisi umum yang biasa dilakukan umat Islam di bulan Ramadhan.
Artikel ini membahas tentang perspektif organisasi Islam di Indonesia dalam menghadapi situasi masa pandemi Covid-19. Apa upaya dan kebijakan yang ditetapkan organisasi tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Artikel ini tidak memuat seluruh upaya organisasi Islam yang ada di Indonesia, namun dibatasi hanya 6 (enam) organisasi saja, yaitu Muhammadiyah,
50 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Nahdlatul Wathan. Ke-enam organisasi tersebut diharapkan mampu mewakili dari sekian banyak organisasi Islam yang ada di Indonesia, yang kesemuanya turut berperan aktif bersama melawan Covid-19, dalam memberikan solusi penanganan dampak Covid-19 di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pembahasan
Wabah Covid-19 bukan saja masalah nasional, tapi sudah menjadi masalah global. Penyebaran virus corona begitu cepat dan mematikan, penularannya melalui kontak fisik, seperti berjabat tangan, cairan dari mulut, hidung, dan mata. Dampak dari wabah Covid-19 adalah timbulnya masalah sosial dan melemahnya perekonomian negara dan masyarakat. Untuk itu dalam penanggulangannya dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama, dalam melawan Covid-19 di Indonesia [19]. Dalam pandangan Islam, wabah semacam virus corona, pernah terjadi di zaman Rasullullah saw, yaitu wabah pes dan lepra. Kebijakan yang dilakukan pada masa itu adalah karantina wilayah, baik ke dalam maupun ke luar wilayah, sehingga virus tersebut tidak menyebar. Untuk kemudian segara dicari anti virus, sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebarannya [20]. Cara penanggulangan tersebut, sama halnya dengan diberlakukan lockdown dan social distancing sebagai solusi dalam menghadapi penyebaran virus corona.
Para pemimpin, termasuk pemimpin organisasi masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan Covid-19 di lingkungannya [21]. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi masyarakat di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap para pengikutnya. Untuk itu Pemerintah tidak dapat sendiri melawan Covid-19, tetapi butuh dukungan dari masyarakat. Berbagai langkah upaya telah dilakukan oleh organisasi Islam di Indonesia, antara lain:
Pertama, organisasi Islam yang dikenal dengan persyarikatan Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menyatakan bahwa Covid-19 merupakan musibah, dan ada beberapa esensi keimanan bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah, diantaranya adalah orang beriman yang semakin yakin pada kekuasaan Allah SWT. Bahwa segala sesuatu tidak pernah lepas dari sunatullah, termasuk hadirnya virus corona di bumi Indonesia. Namun
New Normal, Kajian Multidisiplin | 51
yakinlah bahwa Islam sebagai agama wahyu akan memberikan jawaban atas segala persoalan yang datang [22]. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama memberikan pedoman dalam memandu perilaku dan ketenangan jiwa. Masyarakat membutuhkan panduan agama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdah maupun muamalah.
Berdasarkan pertimbangan dari berbagai masalah yang muncul sebagai dampak dari Covid-19, seperti masalah dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Maka, Muhammadiyah mengeluar-kan “Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah” Nomor 05/EDR/1.0/E/ 2020, tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak Covid-19. Panduan tersebut berisi 6 point yang berisi imbauan pada warga Muhammadiyah untuk memperhatikan status zona (merah/hijau) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan ibadah. Dalam beribadah, hendaknya tetap meng-utamakan pertimbangan kesehatan, kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan sesuai maqasid al-syari’ah untuk menghindari mafsadat dan mengurangi penularan Covid-19. Tuntunan ibadah dan panduan pembinaan keagamaan - peribadatan jama’ah Muhammadiyah dalam masa pandemi Covid-19 tercantum dalam lampiran dari edaran ini [23].
Langkah yang diambil oleh Muhammadiyah dalam menetapkan panduan dan tuntunan ibadah selama masa pandemi Covid-19, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qotadah (2020), yaitu Covid-19: tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap penangguhan pelaksanaan ibadah sholat di tempat ibadah (Hifdz al-Nash lebih utama dari Hifdz al-Din?). Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa pada dalam masa wabah Covid-19 yang merupakan ancaman berbahaya bagi nyawa dan jiwa manusia, maka penangguhan atau larangan pelaksanaan ibadah sholat Jum’at ataupun sholat berjama’ah di Masjid adalah tepat dan selaras dengan penjagaan muqasit shariah yaitu menjaga jiwa yang bertujuan untuk mendatangkan maslahah dan mengelakkan mafsadah yang dapat menimpa manusia [24].
Kedua, adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia, untuk membimbing dan membina kaum muslimin di Indonesia. MUI sangat menyadari tanggungjawabnya sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), khususnya dalam menghadapi wabah Covid-19 dengan istikamah. MUI sangat cepat merespon kegelisahan umat, dalam kurun waktu 16-27 Maret 2020, MUI telah mengeluarkan 3 (tiga) fatwa untuk merespon harapan umat. (1) Fatwa MUI nomor 14 tahun
52 | New Normal, Kajian Multidisiplin
2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. (2) Fatwa MUI nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19. (3) Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19, meliputi tata cara memandikan, mengafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah Covid-19 [25].
MUI juga membentuk satuan tugas (Satgas) dalam menangani wabah Covid-19. MUI berkomitmen memaksimalkan kinerja membantu masyarakat, baik tim medis maupun warga yang terdampak Covid-19. Guna memaksimalkan kinerja Satgas Covid-19, MUI bersinergi dengan pihak terkait, seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Satgas Nasional Covid-19, termasuk dengan jejaring ormas-ormas Islam dan lembaga filantropi. Satgas Covid-19 MUI menyiapkan relawan untuk pendampingan keagamaan secara virtual pada pasien, yang tengah menjalani isolasi, serta menjadi konsultan tempat bertanya masyarakat dalam pengurusan jenazah. MUI juga mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting terkait Covid-19 seperti tentang tidak bolehnya penolakan pemakaman jenazah yang terinfeksi virus corona dan edukasi umat terkait pelaksanaan ibadah selama masa pandemi Covid-19 [26].
Upaya MUI membantu Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini selaras dengan penelitian Mushodiq dan Imron (2020), yang meneliti tentang peran MUI dalam mitigasi pandemi Covid-19: tinjauan tindakan sosial dan dominasi kekuasaan Max Weber. Hasil penelitian mengungkap 7 (tujuh) motif MUI dalam menerbitkan fatwa peribadatan masyarakat muslim saat pandemi Covid-19. (1) MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan. (2) motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan. (3) motif instrumentally rational dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan. (4) MUI menggunakan nilai-nilai agama Islam yang bersumber dari al-Qur’an, hadits, dan kaidah fiqih. (5) MUI berupaya untuk meneruskan tradisi para Nabi dan sahabat. (6) Dominasi kekuasaan MUI penentu hal wajib dan haram dalam peribadatan di Indonesia. (7) MUI sangat penting perannya dalam upaya mitigasi pandemi Covid-19 [27].
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aji (2020) menyatakan bahwa MUI menyikapi kondisi darurat Covid-19 dengan memberikan pandangan terkait sikap peribadatan umat Islam, baik itu kewajiban
New Normal, Kajian Multidisiplin | 53
sholat Jum’at, sholat berjama’ah di masjid, maupun penanganan mayit terinfeksi Covid-19. Pandangan keagamaan yang diberikan MUI diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 [28].
Ketiga, organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Terkait ditetap-kannya Covid-19 sebagai bencana global oleh WHO dan bencana non alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah merasa prihatin dan memohon kepada Allah SWT agar wabah Covid-19 segera berakhir. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan belasungkawa kepada korban Covid-19 yang meninggal dunia, memohon kesembuhan bagi yang sakit terinveksi virus corona, dan memberikan apresiasi bagi tenaga medis, serta semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19. Menimbang betapa cepatnya penyebaran virus corona. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah nyata, cepat, terkontrol, terukur, sungguh-sungguh, terbuka, dan melibatkan semua pihak [29].
Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengeluarkan “Maklumat” nomor: 034-M-03.2020 tantang wabah corona virus (Covid-19). Ada 8 (delapan) point yang disampaikan dalam Maklumat tersebut. (1) Imbauan meningkatkan ketaqwaan, ibadah, dzikir, memohon ampun dan pertolongan kepada Allah SWT agar terhindar dari wabah Covid-19. (2) Menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan diganti dengan kegiatan yang tidak melibatkan banyak orang atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. (3) Imbauan untuk sholat di rumah bagi warga yang sakit, dan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. (4) Imbauan kepada pengurus masjid agar meningkatkan kebersihan dan menyediakan hand sanitizer di berbagai tempat di masjid. (5) Kegiatan Pendidikan di lingkungan Al-Irsyad diselaraskan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah setempat, serta pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Majelis Pendidikan dan Pengajaran. (6) Imbauan membatasi kegiatan di luar rumah, menunda bepergian, dan membatasi kegiatan dengan orang lain yang dikhawatirkan berpotensi menularkan Covid-19. (7) Imbauan menjaga pola hidup sehat. (8) Imbauan agar senantiasa menjalani semua ini dengan sabar dan berpegang pada Islam [29].
Maklumat tentang wabah Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020), yang menganalisis berbagai respon komunitas muslim terhadap wabah Covid-19. Hasil penelitian
54 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mengemukakan bahwa pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalisma, pengaruh teologi Qadariyah membawa pada sikap menerima wabah sebagai musibah, dan pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid Syariah untuk mendahulukan pencegahan mudharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma’ruf nahi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial [30].
Keempat, Dewan Masjid Indonesia (DMI), merupakan salah satu lembaga pengelola masjid di Indonesia yang turut ambil bagian dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. DMI mengimbau kepada ummat muslim untuk menjaga sanitasi masjid dan mushola. DMI menyampaikan imbauannya dengan mengeluarkan Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, nomor 041/PP-DMI/A/II/ 2020. Dalam surat edaran tersebut Pimpinan Pusat (PP) DMI mengimbau kepada seluruh jajaran Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), dan Pimpinan Ranting (PR) agar melakukan langkah-langkah sanitasi siaga bersama-sama dengan Dewan Kemak-muran Masjid (DKM) serta takmir masjid dan mushola [31].
Ada enam langkah sanitasi masjid dan mushola. (1) Pengurus masjid teratur menjaga kebersihan lantai masjid atau moshola dengan cairan desinfektan. (2) Menjaga kebersihan karpet dan alas sholat lainnya dengan rutin atau kontan, dengan menggunakan vacum cleaner atau alat pembersih lain yang dianjurkan. (3) Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan desinfektan. (4) Mengimbau para jama’ah sholat agar membawa sajadah atau sapu tangan serta kain bersih sendiri, sebagai alas sujud masing-masing. (5) Meminta para jama’ah yang sedang batuk, demam, dan mengalami gejala sakit seperti flu dan salesma, agar melaksanakan sholat di rumah hingga sembuh. (6) Pengurus masjid ikut mengawasi penyebaran atau penularan virus corona dan melakukan upaya tanggap atau melaporkan jika ada warga masyarakat yang dicurigai terdampak Covid-19, khususnya di sekitar masjid dan mushola [31].
Langkah preventif yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, dalam menjaga kebersihan masjid dan mushola, agar pelaksanaan ibadah menjadi lebih bersih dan aman, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatna (2020). Dalam Islam wabah virus corona ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini dengan Tho’un yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan beresiko
New Normal, Kajian Multidisiplin | 55
menular [32], untuk meminimalisir penularan virus corona di lingkungan masjid, maka sanitasi siaga penting dilakukan.
Kelima, adalah pandangan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, ada 11 (sebelas) point yang di rekomendasikan ICMI kepada Pemerintah.(1) Pengimplementasian PSBB secara konsisten dan tegas, dengan sanksi yang jelas. (2) Meningkatkan koordinasi dan peran semua kalangan agar mampu memenuhi ke-butuhan pangan secara mandiri. (3) Meningkatkan pengamanan dan dukungan kepada tenaga medis. (4) Memperkuat ketahanan pangan. (5) Menggalang gerakan Nasional untuk mendukung kemandirian ekonomi. (6) Meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. (7) Melibatkan para tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan pencegahan Covid-19, serta perlunya penguatan jiwa raga melalui pendekatan spiritual. (8) Memberikan tugas khusus pada Perguruan Tinggi dan Badan Penelitian, untuk mengembangkan teknologi penanggulangan wabah. (9) Memfokuskan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. (10) Mengedepankan kepentingan Nasional dengan sepenuhnya menggunakan SDM Indonesia. (11) Menghadapi normalitas baru di Indonesia, seperti interaksi online yang lebih dominan, deglobalisasi, dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada UMKM dan UKM agar ketahanan ekonomi lebih kuat dan bertahan [33].
Rekomendasi yang diajukan oleh ICMI kepada Pemerintah, khususnya pada poin ke-1 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnimah (2020). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa langkah-langkah taktis dapat dilakukan dengan cepat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, akan tetapi lambannya pemerintah pusat dalam mengambil komando sangat disayangkan. Peran pemerintah pusat saat ini seolah-olah hanya melakukan beberapa strategi komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif. Kita membutuhkan garansi, bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan jika terjadi sesuatu yang tidak teratasi. Pemerintah pusat harus siap melakukan komando nasional, dan memberikan garansi keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara Indonesia [34].
Rekomendasi ICMI kepada Pemerintah terkait ketahanan pangan di Indonesia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diwangkara (2020). Pemenuhan kebutuhan pangan selama masa pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian khusus, agar ketahanan pangan nasional tetap
56 | New Normal, Kajian Multidisiplin
terjaga. Kebijakan yang diambil pemerintah antara lain: kestabilan harga pangan, perubahan pola rantai pasok pangan, proses distribusi lebih banyak menuju pasar-pasar online, meningkatkan fasilitas produksi dan distribusi, ketersediaan bahan pangan. Optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik, terutama pada masa wabah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri [35] [36].
Rekomendasi ICMI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh diperkuat dengan hasil penelitian Purwanto et al., (2020) yang menunjukkan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh siswa, guru, dan orangtua dalam pembelajaran online, seperti dalam hal lemahnya penguasaan teknologi, biaya kuota internet, pekerjaan tambahan orangtua mendampingi anaknya belajar di rumah, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara guru dan siswa, jam kerja menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dengan orangtua, guru lain, dan kepala sekolah [37].
Rekomendasi ICMI terkait dukungan bagi tenaga medis, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Walton, et al. (2020) yang menyatakan pentingnya mendukung kesehatan mental dan staf medis selama menghadapi pademi Covid-19. Selain itu juga penelitian Rosyanti dan Hadi (2020) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan adalah yang paling rentan terganggu kesehatan mentalnya, seperti stress, perubahan konsentrasi, lekas marah, cemas, susah tidur, berkurangnya produk-tivitas, konflik antarpribadi, pemisahan dari keluarga, situasi abnormal, peningkatan paparan, ketakutan tertular virus, takut membawa infeksi dan menularkan anggota keluarga atau orang lain, diisolasi, perasaan tidak pasti, beban kerja yang berlebih, serta rasa tidak aman ketika memberikan pelayanan da perawatan pada pasien Covid-19. Sedangkan rekomendasi ICMI terkait peran tokoh agama dalam turut serta menanggulangi wabah Covid-19 sejalan dengan penelitian Syafrida (2020), yang menyimpulkan bahwa untuk mencegah penyebaran Covid-19 dibutuhkan dukungan dan kerjasama, antara pemerintah, masyarakat dan tokoh agama untuk saling bahu membahu, bantu membantu, dan mengingatkan satu sama lainnya bersama melawan corona.
Keenam, organisasi pemuda Nahdlatul Wathan (NW). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Syaikhuna Tuan Guru Bajang memandang bahwa Covid-19 ini adalah bentuk ujian dari Allah SWT dengan suatu bala’ yang menimpa seluruh kawasan dunia. Angka penularan dan jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah, hal ini bisa terjadi disebabkan karena masyarakat masih mengabaikan protokol
New Normal, Kajian Multidisiplin | 57
kesehatan dan karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahaya Covid-19, serta bagaimana cara mencegahnya. Nahdlatul Wathan berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi secara umum tentang keberadaan, pola penyebaran dan istilah-istilah terkait Covid-19, harus diperhatikan pula oleh satuan pendidikan di lingkungan sekolah dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Berdasarkan hal tersebut Pimpinan Wilayah Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Buku Saku Protokol Covid-19 sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan [38].
Buku saku yang diluncurkan oleh Pemuda Nahdlatul Wathan berisi 43 halaman yang memuat pedoman dan tata cara menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Penerbitan buku saku tersebut merupakan upaya pemuda NW untuk ikut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB. Buku saku tersebut didistribusikan pada masyarakat di Lombok dan Sumbawa. Untuk tahap awal buku saku baru bisa di cetak sebanyak 3000 eksemplar, namun akan dicetak lagi menjadi 5000 eksemplar. Buku saku tersebut merupakan panduan praktis yang dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin memahami bagaimana cara menjalankan protokol kesehatan yang benar, khususnya bagi tidak memiliki keluangan waktu secara khusus untuk memahami protokol kesehatan Covid-19 [38].
Upaya yang dilakukan oleh Pemuda Nahdlatul Wathan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bahaya dan cara pencegahan penyebaran Covid-19 selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dein, et al., (2020). Dein menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini belum ditemukannya obat dan vaksinasi yang efektif. Negara-negara di seluruh dunia melakukan penguncian (lockdown) secara global dan penerapan social distancing, maka lakukan upaya yang mencegah penyebaran virus corona tersebut. Nahdlatul Wathan merupakan organisasi pemuda di Indonesia yang turut melakukan upaya pencegahan wabah Covid-19.
Penutup
Pada dasarnya organisasi Islam di Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan, antara lain: (1) Muhammadiyah, mengeluarkan edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 05/EDR/1.0/E/2020, tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak Covid-19; (2) Majelis Ulama Indonesia (MUI),
58 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mengeluarkan tiga fatwa, yaitu nomor 14, 17 dan 18, tahun 2020 terkait pelaksanaan ibadah dan fardhu kifayah di masa pandemi covid19; (3) Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengeluarkan Maklumat nomor: 034-M-03.2020 tantang wabah corona virus (Covid-19); (4) DMI mengeluarkan Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, nomor 041/PP-DMI/A/II/2020 tentang langkah-langkah sanitasi masjid dan mushola; (5) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memberikan 11 (sebelas) point rekomendasi kepada Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan (6) organisasi pemuda Nahdlatul Wathan (NW) meluncurkan Buku Saku Protokol Covid-19 sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Ormas Islam di Indonesia sudah berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Mereka telah melakukan ketentuan Pemerintah, seperti memberlakukan PSBB, isolasi mandiri, dan memberikan anjuran dalam pelaksanaan ibadah selama masa Covid-19 [39]. Menurut survey Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang paling peduli terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Ikatan Dokter Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona [40]. Partisipasi masyarakat (ormas) adalah model terbaik dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Melalui jalur agama ternyata lebih efektif di terima oleh masyarakat dalam memberikan solusi menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia dan diharapkan masyarakat dapat menghadapinya dengan tenang, sabar, menerima takdir, dan senantiasa memanjatkan do’a kepada Allah SWT sebagai bagian dari ikhtiar.
Rujukan
[1] A. Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures,” J. Penyakit Dalam Indonesia, vol. 7, no. 1, pp. 45–67, 2020.
[2] I. N. Juaningsih et al., “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 6, pp. 509-518, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363.
[3] Yuliana, “ Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur”, Wellness and Healthy Magazine, vol. 2, no. 1, pp. 187-192, 2020.
[4] N. Shaukat, D. M. Ali, and J. Razzak, “Physical and Mental Health Impacts of COVID-19 on Healthcare Workers: a scoping review”,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 59
International Journal of Emergency Medicine, pp. 1-8, 2020, https://doi.org/10.1186/s12245-020-00299-5
[5] L. Rosyanti, and I. Hadi, “Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan”, HIJP: Health Information Jurnal Penelitian, vol. 12, no. 1, pp. 107-130, 2020, https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/HIJP.
[6] M. Walton, W. Murray, and M. D. Christian, “Mental Health Care for Medical Staff and Affiliated Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic”, European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, vol. 9, no. 3, pp. 241–247, 2020, doi: 10.1177/2048872620922795 journals.sagepub.com/home/acc
[7] S. Hanoatubun, “Dampak Covid–19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, EduPsyCouns, J., vol. 2, no. 1, pp. 146-153, 2020.
[8] Susilawati, R. Falefi, and A. Purwoko, “Impact of COVID-19’s Pandemic on the Economy of Indonesia”, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), vol. 3, no. 2, pp. 1147-1156, 2020, www.bircu-journal.com/index.php/birci, doi: https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954
[9] E. Supriatna, “ Socio-Economic Impacts of The COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City”, J. of Governance, vol. 5, Issue 1, pp. 61-70, 2020, http://dx.doi.org/10.31506/jog.v5i1.8041
[10] R. H. S. Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 395-402, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15314.
[11] Z. H. Duraku, and L. Hoxha, “ The impact of COVID-19 on education and on the well-being of teachers, parents, and students: Challenges related to remote (online) learning and opportunities for advancing the quality of education”, preprint, 2020, https://www.researchgate.net/publication/341297812
[12] W. A. F. Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”, Edukatif: J. Ilmu Pendidikan., Vol. 2 No. 1, pp. 55-61, 2020, [Online]. Available: https://edukatif.org/index.php/edukatif/index
[13] D. Mustajab, et al., “Fenomena Bekerja dari Rumah sebagai Upaya Mencegah Serangan COVID-19 dan Dampaknya terhadap Produktifitas Kerja”, The International Journal Of Applied Business Tijab, vol. 4, no. 1, pp. 13-21, 2020.
60 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[14] S. Dein, at al., “COVID-19, Mental Health and Religion: an Agenda
for Future Research”, Mental Health, Religion & Culture, vol. 23, no. 1, pp. 1-9, 2020, doi: 10.1080/ 13674676.2020.1768725, https://doi.org/10.1080/13674676.2020.1768725.
[15] B. E. Ezziti, B. E. E. Hmidi, and M. E. Hattach, “ Human-Islamic Values and Ramadan: How Muslims Endure the COVID-19 Pandemic during the Period of Quarantine”, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 11, Issue 5, pp. 1345-1349, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342004305, IJSER © 2020 http://www.ijser.org
[16] S. A. Quadri, “COVID-19 and religious congregations: Implications for spread of novel pathogens”, International Journal of Infectious Diseases, pp. 219-221, 2020, https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.05.007 home page: www.elsevier.com/locate/ijid
[17] B. Jati, and G. R. A. Putra, “Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 473-484, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15316.
[18] A. Rochim, “Cegah Penyebaran Corona, 14 Ormas Islam Imbau Masyarakat Tidak Mudik”, 2020, https://nasional.sindonews.com/berita/1578070/15/cegah-penyebaran-corona-14-ormas-islam-imbau-masyarakat-tak-mudik
[19] Syafrida, and R. Hartati, “ Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 6, pp. 555-564, 2020, doi: 10.15408/sjsbs. v7i6.15352.
[20] Mukharom, and H. Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 3, pp. 239-246, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i3.15096.
[21] I. Prawoto, et al., “Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma’had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 402-422, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15571.
[22] C. Anam, “Membaca Ulang Corona dari Perspektif Haedar Nashir, Ketum
New Normal, Kajian Multidisiplin | 61
Muhammadiyah”,https://surabaya.bisnis.com/read/20200429/531/1234178/membaca-ulang-corona-dari-perspektif-haedar-nashir-ketum-muhammadiyah
[23] Edaran PP Muhammadiyah Tentang Tuntunan Dan Panduan Menghadapi Pandemi Dan Dampak Covid-19”, 2020, http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-19148-detail-edaran-pp-muhammadiyah-tentang-tuntunan-dan-panduan-menghadapi-pandemi-dan-dampak-covid19.html
[24] H. A. Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7, pp. 659-672, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15676.
[25] E. J. A. H. Nasution, “MUI Bersama Umat Menghadapi Covid-19”, Pokok MUI, 2020, https://mui.or.id/pojok-mui/27946/mui-bersama-umat-menghadapi-covid-19/
[26] D. A. Noor, “MUI Bentuk Satgas Covid-19 untuk Bantu Tim Medis dan Masyarakat Terpapar Corona”, 2020, https://www.askara.co/read/2020/04/12/3158/mui-bentuk-satgas-covid-19-untuk-bantu-tim-medis-dan-masyarakat-terdampak-corona
[27] M. A. Mushodiq, and A. Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 455-472, 2020, doi: 10.15408/ sjsbs.v7i5.15315.
[28] A. M. Aji, “Pandangan Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Terkait Kewajiban Menjaga Diri, Pelaksanaan Sholat Jum’at dan Pengurusan Mayit Dalam Situasi Darurat Penyebaran Covid-19”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 485-494, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15313.
[29] A. AlIslamiyyah, “Maklumat Tentang Wabah Corona Virus (Covid-19)”, 2020, https://www.alirsyad.or.id/blog/2020/03/16/maklumat-tentang-wabah-corona-virus-covid-19/
[30] N. Hidayah, “Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Pandemi Covid-19 di Indonesia”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 5, pp. 423-438, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15365.
62 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[31] D. F. Dirgantara, “6 Imbauan Dewan Masjid Indonesia untuk
Cegah Penyebaran Virus Corona”, 2020, https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/dimas-fitra-dirgantara/cegah-penyebaran-virus-corona-dewan-masjid-indonesia-imbau-6-hal-ini-regional-sumut/1
[32] E. Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 6, pp. 555-564, 2020, doi: 10.15408/ sjsbs.v7i6.15247.
[33] Rekomendasi Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia Terkait Covid-19, 2020, https://icmi.or.id/media/siaran-pers/rekomendasi-ikatan-cendikiawan-muslim-se-indonesia-icmi-terkait-covid-19
[34] Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, Salam: J. Sosial & Budaya Syar-i, vol. 7, no. 3, pp. 555-564, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i3.15103.
[35] C. Diwangkara, “Upaya Bela Negara Melalui Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19 (Efforts To Defend Countries Through Food Security In The Pandemic Covid-19)”, This preprint research paper has not been peer reviewed. Electronic copy 2020 available at: https://ssrn.com/abstract=3621404.
[36] F. B. Hirawan, and A. A. Verselita, “ Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19”, CSIS Commentaris DMRU-048-ID, 2020.
[37] A. Purwanto, et al., “ Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, EduPsyCouns, J., vol. 2, no. 1, pp. 1-12, 2020.
[38] N. Imansyah, “Buku Saku Protokol Covid-19 diluncurkan Pemuda Nahdlatul Wathan”, 2020, https://kalsel.antaranews.com/nasional/berita/1661914/buku-saku-protokol-covid-19-diluncurkan-pemuda-nahdlatulwathan?utm_source=antaranews&utm_medium=%20nasional&utm_campaign=antaranews
[39] Humas, LIPI, “Peran Agama Dalam Memutus Mata Rantai Covid-19, 2020, http://pmb.lipi.go.id/peran-agama-dalam-memutus-mata-rantai-covid-19/
[40] M. Fakhruddin, “Survei LKSP: Muhammadiyah Paling Peduli Covid-19”, 2020, https://republika.co.id/berita/qcqzcr327/survei-lksp-muhammadiyah-paling-peduli-covid19
New Normal, Kajian Multidisiplin | 65
Bab 5
Psikologi Jawa: Menghadirkan Ajaran Lama Enem Sa dalam Kebiasaan Baru (New Normal) Tri Rejeki Andayani5
Pengantar
Mewabahnya virus baru bernama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengancam jiwa manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia mendorong munculnya berbagai upaya untuk menekan lajunya penularan virus ini. Mulai dari anjuran atau imbauan untuk menjaga jarak fisik, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, pemakaian masker, sampai dengan cuci tangan dengan gerakan yang benar dan mengggunakan air bersih yang mengalir serta sabun. Untuk mendukung penanganan peningkatan kasus positif Covid-19 yang semakin pesat, maka pada tanggal 29 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah. Selanjutnya pada 1 April 2020 Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian muncul pula Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. serta dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) yang resmi menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pusat yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020, serta beberapa kebijakan dari kementerian lainnya.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut lalu diikuti para kepala daerah dengan mengeluarkan berbagai bentuk anjuran dan aturan yang bertujuan untuk membantu pemerintah menangani Covid-19 di wilayahnya masing-masing a.l. Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran
5 Dr. Tri Rejeki Andayani, M.Si., Dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. email: [email protected].
66 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), Surat Edaran (SE) Walikota Surakarta Nomor 443.76/718 tentang Pembatasan Aktivitas Pertemuan Warga Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19, Dengan kata lain, Pandemi Covid-19 telah membawa kita masuk ke dalam tatanan kehidupan baru dengan kebiasaan baru (new normal) yang membutuhkan kesadaran diri untuk melakukan pembatasan dalam beberapa hal. Realitas inilah yang mengingatkan penulis pada Ajaran Enem Sa dari Ki Ageng Soerjomentaram.
Mengenal dan Memaknai Ajaran Enem Sa
Ajaran Enem Sa untuk pertama kalinya penulis kenal dari seorang budayawan besar dan juga berprofesi sebagai psikolog dan ilmuan Psikologi di Indonesia. Beliau adalah Prof. Drs. Darmanto Jatman, SU., guru besar pertama di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip), Semarang pada tahun 2007. Semasa hidupnya, Beliau dikenal sebagai budayawan yang sangat populer, juga sebagai psikolog dan ilmuan di Bidang Psikologi Sosial yang “nyentrik”, anti kemapanan. Psikologi Jawa atau Ilmu Jiwa Jawa merupakan buah pemikiran mendalam Pak Dar tentang ilmu perilaku manusia dalam perspektif Budaya Jawa, terutama dari ajaran dari Ki Ageng Soerjomentaram [1][2].
Ajaran Enem Sa ini merupakan bagian dari Ilmu Kawruh Jiwa dalam Keseluruhan Wejangan Ki Ageng Soerjomentaram (KAS) yang ditulis Jatman [1], atau Ilmu Bahagia menurut KAS yang ditulis ulang oleh Afif [4] bersumber dari tulisan berbahasa Prancis dari Marcel Bonneff berjudul “Ki Ageng Suryomentaram, Prince et Philosophe Javanais,” dimuat pertama kali di Archipel 16 (1978). Tulisan Bonneff ini lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Susan Crossley dengan judul “Ki Ageng Suryomentaraman, Javanese Prince and Philoshoper,” dimuat di Indonesia 57, April 1994 [5].
Hasil penelusuran literatur menunjukkan beberapa tulisan yang telah menyebutkan pentingnya ajaran Enem Sa ini, yakni: sabutuhe, saperlune, sacukupe, sabenere, samesthine, dan sapenake. Namun belum ada yang mengupasnya secara tuntas dalam kaitannya dengan realitas saat ini. Oleh karena itu, dalam tulisan kali penulis ini akan memaparkan secara lebih rinci enam prinsip tersebut agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 67
1. Sabutuhe Prinsip ini berasal kata butuh yang artinya hampir sama dengan
kata perlu. Selintas sudah tampak bahwa prinsip ini terkait dengan kebutuhan manusia. Berdasarkan potensi pemenuhannya, kebutuhan manusia dikenal bersifat dinamis dan hierarkhis meliputi physical needs, safety needs, social needs, esteem needs, dan self actualization sebagaimana dikemukakan Abraham Maslow dalam teorinya Needs Hierarchy Theory [7]. Menurut Maslow seorang berperilaku tertentu karena memiliki dorongan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip pertama dalam Ajaran Enem Sa yakni sabutuhe mengajarkan agar hidup kita agar selalu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, terutama pada kebutuhan dasarnya. Dengan berpegang pada prinsip ini, maka kita tidak perlu mengumbar nafsu mengikuti segala keinginan yang seringkali bukan menjadi kebutuhan utama manusia. 2. Saperlune
Seperti yang dijelaskan pada prinsip pertama, saperlune memiliki kedekatan makna dengan kata sabutuhe. Jika sabutuhe berorientasi pada ukuran fisik, maka maka saperlune merujuk pada kepentingan. Artinya dalam hidup kita cukup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kepentingannya saja, misalnya saat kita harus berkunjung ke tetangga untuk menengok anak tetangga yang sakit, maka cukupkan kunjungan kita untuk mengabarkan keadaan anak yang sakit dan mendoakannya agar cepat sehat kembali, atau memberikan bantuan yang dibutuhkan mereka. Usahakan tidak berlama-lama saat berkunjung, apalagi membicarakan hal-hal lain yang tidak perlu, karena ini hal tidak sejalan dengan prinsip sabutuhe dan saperlune. 3. Sacukupe.
Prinsip ketiga, sacukupe yang berasal dari kata dasar cukup ini dekat dengan prinsip sa yang pertama yaitu sabutuhe. Mengacu pada KBBI online (https://kbbi.kemdikbud.go.id), kata cukup dapat diartikan dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang. Sementara kata secukupnya berarti sebanyak yang diperlukan. Mengutip Lao Tzu, filosof China yang mengatakan bahwa “Orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya” [8]. Lalu bagaimana tolok ukur untuk dapat dikatakan cukup? Apakah hal ini tidak akan subjektif? Memaknai cukup akan menjadi subjektif saat yang menjadi ukuran adalah keinginannya dan bukan kebutuhannya, apalagi jika ditambah dengan menggunakan perbandingan apa yang sudah dimiliki orang lain. Sebaliknya, cukup akan menjadi objektif jika
68 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menggunakan ukuran dari seberapa besar kebutuhannya, bukan keinginannya. Seperti yang diajarkan KAS, bahwa rasa yang bekerja dalam diri orang Jawa sesungguhnya bukan untuk diperbandingkan, melainkan untuk dipahami dan dimengerti oleh pribadi yang bersangkutan [4]. Lebih lanjut dijelaskan KAS, bahwa mengerti rasa (mangertos raos) itu berbeda dengan melihat rasa (sumerep raos). Kalau melihat rasa tidak perlu berpikir, sedangkan mengerti rasa merupakan hasil atau buah pemikiran (mangertos punika wohing pikir). Tidak heran bila ada ungkapan yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa bahwa “Wong Jawa iku nggone rasa ”. Rasa dalam konsep KAS dapat berwujud dalam dua tingkatan, yakni sebagai rasa Kramadangsa dan sebagai rasa manusia tanpa ciri ” [1]. Secara ringkas Prihartanti [3] menjelaskan bahwa rasa sebagai struktur dasar manusia memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi kelengkapan yang menunjukkan rasa sebagai alat yang berupa fungsi penginderaan/fisik, perasaan/emosi, pikiran/kognisi, dan fungsi intuisi. Kedua, dimensi kesempurnaan yang menunjukkan rasa sebagai kemampuan atau tingkat kualitas kesadaran manusia. Tingkatan rasa dalam dimensi ini bisa dangkal dan sempit seperti yang digambarkan sebagai rasa/kesadaran Kramadangsa tadi, dan juga bisa mendalam dan luas jika mencapai kesadaran manusia tanpa ciri. 4. Sabenere
Prinsip ke-4 dari Ajaran Enem Sa yang berasal dari kata dasar bener (benar) ini dapat dipahami melalui tiga kata kunci yang relevan, yakni: (1) benar, artinya tidak salah atau dengan kata lain adalah betul, (2) sebenarnya, artinya sesungguhnya atau sebetulnya, (3) kebenaran yang memiliki arti keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya atau sesuatu yang sungguh-sungguh/benar-benar ada (KKBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id). Dari penjelasan tersebut maka sabenere dapat dimaknai sebagai prinsip yang mengajarkan senyatanya, apa adanya, dan mengandung kebenaran. 5. Samesthine
Berasal dari kata mesthi (harus), jadi semesthine dalam Bahasa Indonesia adalah seharusnya. Mengacu pada KBBI Online (https://kbbi.kemdikbud.go.id) berarti sepatutnya, semestinya, atau sepantasnya. Dengan kata lain, prinsip semesthinya memastikan bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang ada dan pantas dilakukan. Tampak bahwa prinsip samesthine ini bersinggungan dengan prinsip sabenere.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 69
6. Sapenake Prinsip terakhir dari Ajaran Enem Sa ini memiliki kata dasar penak
atau enak, artinya dalam hidup seseorang perlu berpegang pada prinsip sapenake (seenaknya). Namun jangan sampai dimaknai sebagai bentuk egoisme yang membiarkan seseorang berbuat sakepenanake dhewe (seenaknya sendiri) atau sakarepe dhewe (semaunya sendiri). Sapenake merupakan rasa yang tidak hanya mementingkan kenyamanan diri sendiri, tetapi juga kenyamanan orang lain [4].
Lalu bagaimana penerapannya? Misalnya dalam kebutuhan dasar berupa pangan, maka jika kita lapar tentu segera mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan. Namun jika makanan yang ditemukan tidak hanya satu jenis saja, dan dirinya mampu membeli semuanya, maka dirinya akan menyantap sesuai dengan kebutuhan (sabutuhe), secukupnya saja (sakukupe), dan seperlunya saja (saperlune). Meskipun dirinya bisa memilih tempat makan yang mewah dan mahal, namun tetap memilih yang penting makanan itu sehat dan mengenyangkan. Tidak jarang orang memaksa makan di tempat yang mewah demi mengejar keinginan sehingga mengabaikan kemampuan, kekepantasan dan kenyamanan. Saat inilah kita kembali mengingat prinsip sabenere, samesthine, dan sapeknake agar tidak terjebak di tempat makan yang mewah atau mahal, tetapi pada khirnya memberatkan diri dan merasa canggung karena tidak terbiasa. Melalui satu contoh sederhana ini, tampak bahwa enam prinsip dalam Ajaran Enem Sa harus wutuh (satu kesatuan), tidak berdiri sendiri-sendiri.
Sejalan dengan hal itu, menurut Triwikromo [9] ada banyak cara yang harus dilakukan agar orang Jawa tidak hidup dalam situasi yang kokehan atau berlebihan. Jika segala sesuatu masih berada dalam takaran sesuai dengan kebutuhannya, dan memang diperlukan, serta sudah semestinya dilakukan, maka lakukanlah dengan secukupnya dan cara-
70 | New Normal, Kajian Multidisiplin
cara yang sebenarnya dan senyamanannya. Sebagai contoh, saat merasa lapar (luwe), maka makanlah (mangan), tetapi jangan lantas mongan-mangan atau berkali-kali makan. Demikian pula saat mengantuk (ngantuk), maka tampak wajar saja jika kemudian menguap (angop), tetapi jangan lantas ongap-angop (berkali-kali menguap) saja. Kalau sudah begitu seharusnya (semesthine) segera mapan turu (tidur), tetapi jangan lantas tura-turu (berkali-kali tidur). Tampak bahwa tindakan yang semula wajar dan positif jika dilakukan sekali saja sesuai kebutuhan (sacukupe), keperluan (saperlune), kecukupan (sacukupe), dan sudah sepantasnya (samesthine) agar tetap nyaman (sapenake) akan berubah menjadi ketidakwajaran atau hal negatif jika hal itu dilakukan berkali-kali dan meninggalkan prinsip 6Sa. Seperti dalam kasus kebutuhan tidur tadi, maka yang perlu diingat bahwa memilih papan nggo turu (tempat tidur) tetap berpegang pada prinsip samesthine (sepantasnya) saja, meski ada prinsip sapenake buakan berarti harus bermewah-mewah, karena prinsip sapenake ini tidak berdiri sendirian tetapi berkaitan dengan prinsip “sa” lainnya. Tampak bahwa prinsip-prinsip dalam Ajaran 6 Sa sesungguhnya mengajarkan pola hidup yang sederhana.
Pola Hidup Sederhana
Tidak dapat dimungkiri bahwa sebelum Pandemi Covid-19 betapa mudahnya kita menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya saat datang ke pusat perbelanjaan, sehingga mudah tergoda untuk membeli barang atau mengkonsumsi sesuatu yang kadang bukan karena kebutuhan tapi lebih pada keinginan. Tidak dimungkiri bahwa keberlimpahan materi dan kelonggaran waktu yang kita miliki acapkali meningkatkan hasrat akan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan sehingga jauh dari kesederhanaan [6]. Sementara sejak Pandemi Covid-19, maka pola hidup kita mengalami perubahan, daam segala aspek kehidupan, terutama dalam kegiatan ekonomi dan relasi. Terkait dengan ekonomi, tidak sedikit orang yang terdampak pandemi secara langsung sehingga mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kehidupan mereka yang sudah terbatas pada awalnya menjadi semakin sulit pada saat ini. Sementara sebagian lainnya secara ekonomi mungkin saja tidak terdampak langsung pada pendapatan, tetapi turut merasakan dampak akibat pembatasan sosial maupun fisik yang telah diterapkan. Keluar rumah seperlunya saja, secukupnya dan utamanya pada hal-hal yang menunjang kebutuhan pokok. Keperluan rekreatif mau tidak mau dibatasi dan kebiasaan yang berlebihan dalam menggunakan sumber daya, baik material (uang atau barang), maupun
New Normal, Kajian Multidisiplin | 71
non-material seperti waktu, jasa, dan kesenangan lainnya mau tidak mau terbatasi pula. Dengan kata lain, hidup mulai harus kembali cermat, hemat, dan tepat dalam segala hal. Keterbatasan di masa Pandemi Covid-19 ini sudah semestinya menjadi momentum untuk membangun dan menguatkan kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelompok masyarakat yang masih berkecukupan secara ekonomi diharapkan semakin memiliki kepedulian pada kelompok masyarakat yang kesulitan hidupnya. Hidup hemat, cermat, dan tepat dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki sejalan dengan prinsip pola hidup sederhana. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan utama. Setelah kebutuhan dasar dipenuhi, kebahagiaan tidak lagi ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki [8].
Dalam perspektif agama Islam, pola hidup sederhana sejatinya telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Saw. Berdasarkan salah satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw sangat sederhana dalam hal berpakaian, tempat tinggal, maupun makanan. Meskipun Allah Swt menawarkan emas sebanyak butiran pasir di gurun kota Makkah kepada Rasulullah, namun Beliau tidak pernah silau dengan kenikmatan duniawi. Dalam konsep Islam, kesedehanaan ini dekat dengan apa yang disebut zuhud. Namun zuhud menurut Nabi Muhammad Saw merupakan jalan tengah atau i’tidal dalam menghadapi segala sesuatu, bukan berarti meninggalkan urusan dunia sama sekali, tetapi mengingatkan manusia untuk tidak terlena dengan keindahan duniawi. Sebagaimana Beliau pernah bersabda dan diriwayatkan dalam salah satu hadist bahwa “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramal-lah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi” [10].
Menurut Al-Ghazali [11] orang yang zuhud memiliki tolok ukur sederhana dalam pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal makanan, Al Ghazali menekankan pada tiga pertimbangan, yakni jenis makanan, waktu menyantap, dan kuantitas atau jumlah yang disantap. Orang zuhud akan mengonsumsi secukupnya makanan sekedar menahan lapar dan menambahkan kekuatan pada tubuh agar dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan sempurna. Dari aspek pakaian, Al-Ghazali membaginya menjadi tiga tingkatan, yakni pakaian rendah dengam harga murah dan tidak brkualitas, pakaian sederhana, dan pakaian tingkat tinggi yang
72 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mahal dan mewah. Orang zuhud akan memilih pakaian dengan tujuan untuk melindungi diri dari cuaca panas atau dingin, bukan dengan tujuan untuk brmewah-mewah, sehingga pakain yang dipilih cenderung sederhana dan tidak perlu mahal. Demikian pula dalam hal tempat tinggal. Orang zuhud memilih tempat tinggal yang memudahkan mereka untuk beramal dan beribadah pada Allah Swt sehingga yang diutamakan adalah kebersihan dan kemudahan untuk mendapat tempat untuk ibadah, bukan kemewahannya. Dengan kata lain, zuhud mengajarkan manusia untuk hidup sederhana. Kesederhanaan yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berperilaku secara berlebihan, dan menghamba pada materi.
Pola hidup sederhana juga membiasakan kita cerdas dalam
mengambil keputusan, tidak bersikap boros karena terbiasa hemat dan cermat dalam mengelola sumber daya, serta membiasakan kita lebih pandai bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, sehingga hidup menjadi lebih tenang dan bahagia [12]. Dan kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita inginkan, melainkan menginginkan apa yang sudah kita miliki dan bahagia juga tidak mengejar kepuasan, tetapi mensyukuri apa yang sudah dimiliki [6].
Penutup
Untuk dapat mengubah perilaku tentu saja tidak dapat dipisahkan dari tata nilai yang diyakini seseorang ataupun sekelompok orang. Sebagai salah satu nilai-nilai hidup, maka sudah saatnya Ajaran Enem Sa kita hadirkan kembali sebagai bagian dari tata nilai dalam kebiasaan baru yang mencerminkan pola hidup sederhana, yang dekat dengan kehidupan orang-orang zuhud. Melatih hidup sederhana dapat diajarkan orang tua kepada anak-anak sejak dini dan dimulai dari cara mengenali dan membedakan antara apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan-nya, dan apa yang merupakan keinginan. Dengan kata lain, sederhana
New Normal, Kajian Multidisiplin | 73
mengarahkan anak pada perilaku yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenar-benarnya, senyatanya, dan apa adanya sejalan dengan prinsip (sabenere). Hidup yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan utama yang sejalan dengan prinsip sabutuhe. Dengan demikian, anak akan terbiasa untuk melakukan segala sesuatu seperlunya dan secukupnya saja (saperlune dan sacukupe), tidak terjebak untuk berfoya-foya atau bermegah-megah demi menuruti keinginannya, karena mempertimbangkan kepatutan dan kenyamanan (samesthine dan sapenake). Selain itu, pola hidup sederhana juga melatih kemampuan anak untuk mengelola apa yang sudah dimiliki dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya, baik bagi dirinya maupun orang lain [13].
Rujukan
[1]. Darmanto, Jt. Psikologi Jawa. Yogyakarta: Bentang Budaya. 1997. [2]. Darmanto, Jt. Psikologi Jawa Jangkep. Semarang: Limpad. 2004. [3]. Prihartanti, N. Kepribadian Lintas Indigenus Lintas Budaya. Surakarta:
Muhammadiyah University Press. 2019 [4]. Afif, A. Ilmu Bahagia Menurut Ki Ageng Suryomentaram. Sleman:
Pustaka Ifada. 2012. [5]. Ki Ageng Suryomentaram: Pangeran dan Filsuf dari Jawa (1892-
1962) Bagian II. Posted by Marcel Bonneff (https://langgar.co/ki-ageng-suryomentaram-bagian-ii/), diunduh 20 Juli 2020.
[6]. Anwar, D. Hidup Sederhana. Jakarta: PT Gramedia. 2015. [7]. Maslow, A.H. A Theory of human motivation. Psychology Review,
Vol.50 (4), 370-396. 1943. [8]. Jay, F. Seni Hidup Minimalis. Jakarta: Kompas Gramedia. 2019 [9]. Triwikromo, T. Kokehan. Kolom Pringitan di Suara Merdeka,
Minggu, 21 Oktober 2018. [10]. Hidayati, T.W. Perwujudan Sikap Zuhud dalam Kehidupan.
Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol. 1(2), 91-106. 2016.
[11]. Ismail, A.M. Konsep Zuhud Menurut Imam Ghazali. Proceeding International Conference On Islamic Educations. Selangor: UKM. 2014.
[12]. Sumarti, Roshonah, A.F., Yifiarti, Maznah, N., Widiati, Y., & Perwitasari. Seri Pendidikan Orang Tua: Membiasakan Hidup Sederhana (Penyunting: Agus Mohamad Solihin, Suradi). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018.
[13]. Solihin, A.M., Prabowo, Y.T., Zakaria, M.R., & Hayati, L.Seri Pendidikan Orang Tua: Menanamkan Hidup Sederhana. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 75
Bab 6
Menggagas Edukasi Masyarakat Era New Normal Akhsanul In’am6
Pengantar
Istilah New normal pernah digunakan sebelum era pandemi covid-19, pada tahun 2007-2008, ketika terjadi krisis keuangan juga telah digunakan istilah new normal, sebagai cara untuk mengatasi pola hidup pasca krisis terjadi, demikian juga pada tahun 2008-2012 setelah terjadinya resesi global juga digunakan istilah tersebut yang tiada lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melaksana-kan sesuatu kebiasaan yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya[1]–[3].
Terjadinya pandemi Covid-19 telah membuyarkan pola tatanan kehidupan seperti yang telah dilakukan sebelumnya [4]. Tidak ada kebiasaan untuk selalu dan sering cuci tangan setelah sebelum dan setehah aktivitas, yang bermakna kurang memperhatikan kebersihan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Penggunaan masker sehari-hari sebagai salah satu cara menjaga kesejahatan agar tidak tertular virus maupun menularkan virus, khususnya corona. Kehidupan dengan menjaga jarak antara individu, adat bersalaman ketika bertemu dengan yang lain pun sekarang ditiadakan, bercengkerama dengaan minum teh atau kopi sambil bincang-bincang ringan yang biasanya dilakukan untuk menunggu waktu tertentu sudah tidak lagi dilakukan, semuanya dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kesehatan [1]–[3], [5]–[8].
Usaha lain, untuk menekan dampak yang timbul karena pandemi covid- 19 selalu dilakukan, salah satunya melalui istilah yang sebelum ini pernah digunakan, new normal.[3], [9]. Suatu pola hidup yang tetap menjaga tatanan agar tidak tertular dan menularkan virus dengan mengurangi dampak negatif, dalam berbagai interaksi kehidupan.
Kehidupan selalu berkembang dan berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Setiap makhluk hendaknya selalu siap dengan perubahan, khususnya sebagai makhluk terbaik di dunia, harus selalu mempersiapkan diri dengan adanya perubahan. Perubahan yang terjadi dapat berbentuk fisik maupun non-fisik, keduanya dapat
6 Prof. Akhsanul In’am, Ph.D., Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Muhammadiyah Malang. Email:[email protected]
76 | New Normal, Kajian Multidisiplin
disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan yang berdampak juga pada pola pikir. Pertumbuhan dan perkembangan pola pikir juga berdampak dalam melihat sesuatu perubahan.
Pertumbuhan pola pikir bermakna bahwa arah pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan dapat mengalami perluasan solusi dari permasalahan yang sedang dan juga selalu dihadapi. Sedangkan perkembangan pola pikir bermakna adanya tinjauan yang multi dimensi dalam usaha mencari solusi dari suatu permasalahan yang hendaknya diselesaikan. Kuantitas dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan pola pikir dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah, baik hal tersebut direncanakan atau pun disebabkan oleh sesuatu yang tidak dikehendaki atau direncanakan [10], [11].
Permasalahan yang terjadi di China, dan mengakibatkan adanya permasalahan yang mendunia, sebagian dikatakan bahwa hal tersebut disebabkan kebiasaan yang kurang tepat masyarakat di Wuhan dalam memanfaatkan makhluk hidup sebagai santapan dan kesukaan [8], [12]. Namun sebagian yang lain, didasarkan dengan beberapa data dan argumen, bahwa kondisi tersebut sepertinya sudah direncanakan sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan bisnis tertentu.
Carut marut penyebab pandemic covid-19 memang silang sengkarut, rumit untuk dipaparkann dan diuraikan, mana yang dapat dipercaya dan mana yang sebenarnya terjadi [13], [14]. Terlepas dari kondisi tersebut, fakta yang ada bahwa covid-19 telah mengglobal dan menjadikan lebih dari 100 negara berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai usaha yang dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing negara.
Dampak yang ditimbulkan covid-19 memang sangat luar biasa, khususnya masalah kesehatan [8], [12], [15]. Namun dampak pengiring juga sangat luar biasa, jika suatu negara tidak terlalu kuat dalam hal ekonomi, menjadi masalah yang besar dalam mengatasi permasalahan tersebut. Memperhatikan dan menyimak solusi yang dilakukan oleh beberapa negara, dapat dikatakan beragam, hal ini tentu disebabkan adanya perbedaan kondisi geografis dan kekuatan ekonomi masing-masing negara. Demikian juga berkaitan dengan tingkat pendidikan dari masing-masing negara.
Sebagian solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi per-masalahan tersebut adalah mengurangi interaksi antar individu dalam masyarakat, termasuk interaksi dalam hal pergerakan perekonomian [1], [16]. Namun fakta yang ada sebagian besar negara-negara terdampak
New Normal, Kajian Multidisiplin | 77
tidak dapat membiarkan kondisi ekonomi, inilah solusi pilihan. Sebagian mengatakan, urusan nyawa tidak dapat ditunda, sebab kematian tidak dapat dihidupkan lagi, sedangkan kebangkrutan ekonomi dapat ditumbuh kembangkan kemudian. Meski demikian, melalui berbagai pertimbangan dan diskusi yang panjang, banyak solusi yang ditawarkan oleh para pakar, bahwa penyelesaian masalah ini dapat dilakukan melalui pola hidup baru, dengan cara tetap pada usaha menjaga kesehatan dan tidak mengkesampingkan kondisi perekonomian tidak teranggu. Disinilah muncul istilah new normal, sebuah tatanan kehidupan baru yang mengikuti protokol kesehatan dalam melaksanakan ke-hidupan sehari-hari dengan tetap melaksanakan roda perekonomian [3], [9], [17]. Memang bagi mereka yang kehidupanya ditopang dari gaji bulanan tidaklah bergitu terasa dampak covid-19. Namun bagi pekerja yang mempertaruhkan kehidupan dari berjalannya roda perekonomian sangat memerlukan dan membutuhkan kehidupan yang dapat menum-buh kembangkan roda perekonomian.
Berbagai tatanan baru, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan, seperti interaksi antar individu dalam masyarakat, edukasi kehidupab bermasyarakat, tatanan pola interaaksi antara pekerja di tempat kerja serta yang paling menyorot perhatian adalah bidang pendidikan yang mempunyai dampak ke berbagai lini kehidupa. Aspek-aspek tersebut hendaknya perlu dibincangkan, dan pemaparan ini mengurai berbagai hal dalam menyongsong pemberlakuan new normal.
Pembahasan
Pola kehidupan baru hendaknya perlu dipahami, direncanakan, diiemplemantasikan dan selalu dievaluasi [11], [18], [19]. Tatanan baru yang disebut dengan new normal, dapat terjadi diperbagai tatanan kehidupan, di rumah, masyarakat, tempat kerja dan juga di tempat pendidikan.
Pola Hidup Keluarga
Kebiasaan yang dilakukan di rumah tangga dapat dikatakan sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh kondisi masing-masing keluarga yang majemuk, hal ini disebabkan oleh kondisi perekoniman yang beraneka [1], [2]. Bagi masyarakat ekonomi atas, kehidupan rumah tangga dapat dikatakan relatif menjaga berbagai hal berkenaan dengan urusan kesehatan dan makanan. Masalah kesehatan, mereka jelas sangat memperhatikan dan preventif dan urusan makanan juga menjadi perhatian dengan memperhatikan asupan gizi yang seimbang untuk
78 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menjaga kesehatan. Sehingga dengan tatanan hidup baru yang disebut dengan new normal, sesungguhnya bagi mereka sudah terbiasa, kecuali beberapa kebiasaan, seperti makan diluar [20], refreshing di tempat rekreasi harus mempertimbangkan aturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan.
Bagi masyarakat dalam tatanan ekonomi menengah, perlu dipahami beberapa aturan dalam memasuki tatanan new normal. Pola kehidupan mereka yang berada pada posisi ini sangat variatif, tergantung kebiasaan yang dilakukan dalam menjaga kesehatan khususnya, meski dalam hal yang berkait dengan makanan relatif terjaga. Kenapa masalah kesehatan kurang memperoleh perhatian, sebab kebanyakan adanya kesempatan untuk meningkatkan pendapat-an kadang kurang memperhatikan masalah kesehatan dan dampaknya juga kurang memperhatikan masalah makanan meski sarana untuk itu tersedia. Memperhatikan yang demikian, sangat diperlukan adanya pemahaman bahwa tatanan kehidupan baru memerlukan pemahaman dan perencanaan agar dalam implementasi dapat berjalan dengan tatanan new normal.
Namun yang perlu memperoleh perhatian jika memperhatikan kehidupan keluarga dari selain paparan diatas. Urusan kebutuhan primer saja biasanya perlu memperoleh perhatian yang berlebih, kerja sehari belum tentu dapat digunakan untuk kehidupan mereka yang layak pada hari itu [21]. Mereka bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan, namun aktivitas yang dilakukan untuk menyambung hidup. Memperhatikan yang demikian, biasanya urusan makanan yang prinsip dapat menyambung kehidupan, sehingga jika memasuki era new normal, mereka perlu memperoleh perhatian yang lebih dari pengambil kebijakan, agar dapat memperhatikan dan setidaknya mengetahui dan dapat melaksanakan protokol kesehatan.
Urusan kebutuhan primer saja mereka mengalami per-masalahan, selain makan, sandang dan papan juga menjadi catatan tersendiri [4], [21]. Berkenaan dengan sandang dan papan, berkaitaan dengan hal kesehatan. Usaha yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ini perlu dilakukan literasi secara berkelanjutan, sehingga dalam memasuki era new normal dapat menyesuaikan diri.
Tatanan Kehidupan di Masyarakat
Membincangkan aktivitas yang ada dimasyarakat, juga berkaitan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 79
berkenaan dengan makanan, pakaian dan kesehatan. Masyarakat hendaknya memperhatikan betul langkah-langkah yang hendaknya ketika belanja kebutuhan sehari-hari [1], [2], [22]. Terdapat sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui belanja di pasar tradisional dan sebagian yang lain di pasar modern, dan sebagian lagi melalui online [20]. Secara umum dapat dikatakan bahwa pasar tradisional yang ada di Indonesia mayoritas tidak memperhatikan jaga jarak antar pembeli, maupun antar pembeli dan penjual. Namun beberapa pasar tradisional sudah banyak yang memperhatikan tatanan kehidupan selama covid-19, misal tempat antar pedagang dibuat zik zak yang memungkinkan pembeli tidak bergerombol. Sedangkan untuk pasar modern juga sebagian sudah menerapkan tatanan kehidupan baru. Meski demikian, pihak pemerintah hendaknya selalu melakukan pengawasan sehingga aturan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Secara umum permasalahan yang ada tidak konsistennya pemerintah untuk mengawal pelaksanaan kehidupan tatanan baru, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan ini tergantung pada daerah masing-masing.
Perbincangan dalam kehidupan di masyarakat selanjutya adalah kehidupan dalam melaksanakan ibadah. Pelaksanaan ibadah yang dilakukan, dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pelak-sanaan ibadah yang dilaksanakan pada tatanan masyarakat dengan kesadaran pendidikan relatif tinggi, pelaksanaan ibadah dapat dilak-sanakan sesuai dengan prosedur yang telah disarankan oleh Pemerintah. Namun jika menilik pelaksanaan ibadah di masyarakat dalam kategori pen-didikan kurang maju, atau dapat dikatakan di daerah pedesaan maka agak tidak mematuhi prosedur tetap yang seharusnya dilaksanakan dalam tatanan hidup baru. Meski sebagian sudah mengikuti prosedur, namun permasalahan penyediaan fasilitas kesehatan dan juga jaga jarak dalam pelaksanaan ibadah agak kurang diperhatikan.
Kondisi tersebut perlu ada solusi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan pemahamann kepada masyarakat dan mengawal pelaksanaan ibadah di tempat-tempat yang belum memenuhi standad, yang hal ini disebabkan oleh pemahaman yang berbeda terhadap pandemik covid-19. Beberapa tokoh masyarakat mengguna-kan logika yang membandingkan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Pasar tempat yang tidak boleh dikatakan selalu bersih, dan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai hal diperkenankan, sedangkan masjid adalah tempat suci dan
80 | New Normal, Kajian Multidisiplin
semua yang beribadah memohon kepada Allah, malah tidak diper-kenankan. Hal ini sungguh diluar nalar sehat, meski demikian, masyarakat memahami apa yang dilakukan pemerintah sebagai cara untuk menyelematkan perekonomian warga. Selain itu, melalui ibadah ditempat yang suci, sesungguhnya lebih baik dan usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan wabah ini, demikian pandangan masyarakat. Sebagai usaha untuk melaksanakan kehidupan new normal, langkah yang tepat dengan memberikan pemahaman berkenaan apa yang hendaknya dilaksanakan agar terhindar dari covid-19 melalui tatanan hidup baru dengan istilah new normal.
Selain hal tersebut, terdapat kebiasaan umat muslim yang mempunyai jamaah pengajian yang dilaksanakan secara periodik, ada yang mingguan, bulanan dan juga selapanan (35 hari). Bentuk kegiatan misalnya, yasinan, tahlilan, berjanji, manaqib, dan juga pengajian rutin. Berbagai kegiatan tersebut biasanya kurang memperhatikan hal-hal yang menjadi standar protokol kesehatan di masa era new normal, seperti saling bersalaman, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker. Sebagai usaha untuk memberikan literasi kehidupan pada tatanan baru, pihak yang berwenang perlu bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan pemahaman dan agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang seharusnya dilaksanakan.
Kehidupan menjadi lebih nyaman dan badan menjadi lebih sehat, sudah seharusnya olah raga dapat dilakukan secara rutin. Kegiatan olah raga yang dilakukan masyarakat sangat bervariasi. Sebagian masyarakat sangat senang olah raga yang berkaitan dengan kompetisi, dan ada sebagian yang tidak berkompetisi. Olah raga yang sifatnya kompetisi, sangat senang dan dilakukan oleh anak-anak muda atau yang berjiwa muda. Menurut para pakar, olah raga yang sifatnya kompetisi tidak baik bagi mereka yang sudah menginjak usia 50 thn ke atas.
Apapun jenis olah raga yang dilaksanakan hendaknya meme-nuhi standad pelaksanaan, dan boleh jadi memilih olah raga yang sesuai dengan memperhatikan jaga jarak, Beberapa olah raga yang hendaknya dihindari misalnya, sepak bola, pencak silat. Namun meski beberapa olah raga yang sifatnya kompetisi dapat dilaksanakan misalnya tenes meja, tenes lapang. Jika boleh dilakatakan, sesungguhnya olah raga yang sifatnya tidak kompetisi, misalnya jogging lebih baik untuk dilaksana-kan untuk menjaga kesehatan. Namun juga terdapat olah raga yang sifatnya tidak kompetisi, namun sangat disarankan untuk dilaksanakan,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 81
antaranya olahraga Gym, yang banyak interaksi menggunakan alat yang banyak digunakan oleh beberapa orang. Memperhatikan yang demi-kian, usaha menjaga kesehatan melalui olahraga sangat baik untuk dilaksanakan, dengan catatan perhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus yang sangat tidak dikehendaki.
Kebiasaan di Tempat Kerja
Aktivitas kerja sangat bervariasi, hal ini tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalankan dan ditekuni oleh masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai wiraswasta dengan berbagai tingkatan, termasuk wira swasta yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaanya sebagai langkah menyambung hidup dan sebagian yang lain merupakan aktivitas investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk generasi yang berikutnya. Selain itu, juga ada jenis pekerjaan yang ditekuni dengan memperoleh dampak dari pekerjaan-nya yang diterimakan secara rutin, misal pegawai, baik negeri maupun swasta.
Bagi masyarakat dengan pekerjaan yang ditekuni adalah wira-swasta, sudah sepatutnya dalam memasuki era new normal akan tergantung dari jenis pekerjaannya, secara prinsip hendakya benar-benar diikuti yang harus ditaati dalam melaksanakan kehidupan pada tatanan new normal. Masyarakat yang aktivitasnya sebagai pekerja, baik perusahaan swasta atau sebagai pegawai negeri, aturan interaksi antar pegawai dan juga jika berada pada bagian pelayanan, hendaknya benar-benar memperhatikan aturan kerja yang diterapkan, terutama masalah kesehatan.
Terdapat pekerjaan rumah yang sangat rumit untuk mencari solusi bagi mereka sebagai pekerja musiman. Menurut pandangan mereka, dapat pekerjaan saja merupakan suatu anugerah yang tiada terkira, dan pendapatan mereka bukanlah untuk menjadi kaya raya, namun untuk menyambung hidup diri dan keluarga [21]. Disinilah peran pengambil kebijakan sangat dominan untuk menertibkan para pekerja ditempat kerja masing-masing melalui pemahaman berkelan-jutan pentingnya menjaga kesehatan dan langkah-langkah preventip agar selalu sehat dan tidak timbul gejala-gejala sebagai indikator terserang virus.
Perbincangan berkenaan dengan mereka yang bekerja dengan gaji rutin alias setiap bulan pendapatan mereka dapat diterima, baik sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta hendaknya mem-perhatikan protokol kesehatan yang hendaknya dilakukan. Keleng-
82 | New Normal, Kajian Multidisiplin
kapan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, masker betul-betul diperhatikan dan saya yakin pastinya tersedia di di tempat kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana model tempat duduk di tempat kerja dan interaksi antar pegawai. Hal ini perlu ada penataan tersendiri untuk menjaga pelaksanaan protokol kesehatan. Namun bagi mereka yang pekerjaannya pada bagian pelayanan, hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius, agar tempat kerja bagian pelayaan benar-benar sudah memenuhi standad pelayanan pada masa new normal, seperti jaga jarak, penggunaan masker, adanya tabir antara yang bertugas melayani dengan mereka yang membutuhkan pelayanan [17], [23].
Edukasi di Institusi Pendidikan
Pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara luring, dan mayoritas semua lembaga penddikan melaksanakan pem-belajaran secara luring dan hanya sebagian kecil pelaksanaan pem-belajaran secara daring. Sebagian lagi melaksanakan pembelajaran secara kolaborasi antara daring dan luring, yang dikenal dengan pembelajaran blended [24]. Namun, adanya pandemi covid-19 semua hal terjadi perubahan yang signifikan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, yang sebagai usaha untuk tetap melaksanakan pembelajaran dan menghambat lajunya penyebaran virus yang agak susah dibendung [4]. Melalui kegiatan pembelajaran daring, merupakan usaha untuk tidak adanya interaksi langsung antara guru aau dosen dan peserta didik atau mahasiswa, dan juga antara peserta didik atau mahasiswa.
Memang, ketika pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring, sadar atau tidak semua yang terkait harus dapat menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang dapat me-laksanakannya. Berbagai permasalahan siilih berganti bermunculan yang disebabkan oleh kondisi yang berbeda antara satu dengan lainya. Terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan jaringan yang tidak tersedia, atau juga jaringan tersedia namun kondisi ekonomi dari pengguna yang menjadi permasalahan. Sebagian yang lain muncul permasalahan berkenaan dengan sumberdaya manusia yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Belum lagi, penyediaan materi yang harus disampaikan kepada peserta didik atau mahasiswa, ada yang belum siap agar penyampaian materi sesuai dengan perencanaan.
Secara sadar dapat dikatakan, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring tanpa adanya persiapan yang matang, disebab-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 83
kan adanya pandemi covid-19 tidaklah maksimal hasil yang diper-olehnya [6]. Bahkan ada juga pengambil kebijakan yang akhirnya mengatakan, lebih baik menyelamatkan nyawa, meski pembelajaran tidak dapat diperoleh secara maksimal, sebab nyawa tidak dapat di-upgrade, sedangkan pembelajaran masih dapat dikejar dengan beberapa strategi.
Menyongsong pelaksanaan era new normal, dan berdasarkan pengalaman pembelajaran daring selama pandemi covid-19 diperlukan persiapan yang relatif matang dengan memahami kondisi pembelajaran yang berbeda. Memperhatikan yang demikian diperlukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi baru, demikian juga pelak-sanaan yang sesuai dengan konteks dimana berada institusi pendidikan sebagai pelaksana pendidikan. Terlepas dari pandemi covid-19, sesung-guhnya sudah diingatkan oleh para pakar berkenaan dengan munculnya era-baru, revolusi industri 4.0. Disadari atau tidak, berbagai sektor ekonomi sekarang ini lebih menggeliat melalui teknologi. Kegiatan pemenuhan kebutuhan keluarga, dapat dilakukan secara online, pem-belian barang-barang keperluan yang sifatnya primer maupun sekunder dapat dilakukan secara online [20]. Meski timbul kegelisahan dengan kondisi tersebut, mau atau tidak mau akan terlewati oleh generasi sekarang, sehingga timbul kegelisahan berkenaan dengan berkurangnya kebutuhan sumberdaya manusia yang tergantikan dengan mesin.
Memperhatikan yang demikian, muncullah society 5.0, suatu kondisi yang mengkaji dan membincangkan bagaimana sumberdaya manusia dapat menyiapkan dan tetap memanusiakan manusia dan dapat menggunaka teknologi untuk kemanfaatan kehidupan yang lebih beradab. Kondisi ini sejalan dengan masa yang sekarang sedang gencar dipromosikan diseluruh dunia, masa new normal. Sebagai bentuk penyiapan diri, khususnya dalam institusi pendidikan [4], [24], terdapat beberapa hal yang hendaknya disiapkan, agar pelaksanaan masa new normal dapat berjalan sebagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang dicanangkan. Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menyiapkan pembelajaran dalam masa new normal dapat dikemukakan seperti berikut: 1. Perencanaan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan model
pembelajaran yang akan dilaksanakan, guru atau dosen sudah seharusnya menyesuaikan tujuan, pelaksanaan dan evaluasi yang diimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan tidak meninggalkan prosedur pengamanan kesehatan.
84 | New Normal, Kajian Multidisiplin
2. Diperlukan adanya kemampuan dibidang teknologi, khususnya
pembelajaran daring bagi guru atau dosen, hal ini dapat dilakukan melalui workshop untuk mengenalkan dan memberikan bekal pelaksanaan pembelajaran daring. Dapat juga disiapkan tenaga yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran melalui daring, hal ini disebabkan terdapat sebagian guru atau dosen yang relatif ada kesulitan untuk ditingkatkan kemampuanya dalam hal pembelajaran daring.
3. Sarana dan prasarana pelaksanaan pembelajaran daring perlu disiap-kan, baik bagi guru atau dosen juga untuk peserta didik atau mahasiswa. Hal ini juga menyangkut masalah pembiayaan yang perlu dicarikan solusi jika terdapat permasalahan, dan juga sam-bungan internet juga perlu dipertimbangkan. Keberhasilan pem-belajaran salah satu faktor penentu adalah sarana dan prasarana, untuk itulah perlu dipertimbangkan secara detil dan dibincangkan berbagai kemungkinan yang tergantung kepada kondisi masing-masing institusi yang sangat beragam.
4. Keberhasilan pembelajaran juga tergantung pada seberapa lama pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Waktu yang tersedia dalam interaksi pembelajaran mempengaruhi berbagai kesiapan lainya, baik guru atau dosen, peserta didik atau mahasiswa, sarana dan prasarana. Memperhatikan yang demikian perlu dirancang sedetil mungkin, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan faktor-faktor pendukung tidak ada kendala.
Penutup
Dampak yang ditimbulkan covid-19 meliputi segala segi kehi-dupan manusia dan hingga hari ini belum ditemukan vaksin yangd apat menangkalnya. Usaha yang dilakukan oleh hampir semua negara yang terdampak, akan memberlakukan tatanan hidup baru yang dikenal dengan New normal. Sebuah tatanan yang memperhatikan berbagai aspek agar kehidupan terhindar dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Hasil analisis yang dilakukan oleh para pakar, menunjukkan bahwa virus corona belum bisa ditemukan obatnya, namun penyelesaian yang dapat dilakukan melalui cara hidup baru yang dapat mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran virus corona. Berbagai tatanan hidup baru dari segala aktivitas hidup didunia dicarikan solusi untuk menangkal virus terseebut. Bidang ekonomi, sosial budaya, bidang pendidikan dan berbagai bidang kehidupan, manusia diedukasi dengan literasi yang menjadikan setiap aktivitas pada bidang-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 85
bidang tersebut mengikuti protokol kesehatan sebagai langkah mengurangi dan bahkan menghentikan penyebaran virus corona. Sebagai langkah utama untuk tidak melebarkan penyebaran virus melalui edukasi kepada masyarakat yang majemuk dari sisi pendidikan, pendapatan, lingkungan kerja dan pemahaman terhadap sebuah penyakit. Langkah yang tepat, kita semua ikut terlibat untuk melakukan edukasi kepada diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dalam memasuki era new normal.
Rujukan
[1] UNCTAD, “Circular Economy: The New Normal?,” United Nations Conf. Trade Dev., vol. 2021, no. 61, 2018.
[2] J. Zhang and J. Chen, “Introduction to China’s new normal economy,” Journal of Chinese Economic and Business Studies, vol. 15, no. 1. 2017.
[3] G. Lawton, “The new normal,” New Sci., vol. 241, no. 3213, 2019. [4] Z. Zaharah and G. I. Kirilova, “Impact of Corona Virus Outbreak
Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia,” SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i, vol. 7, no. 3, 2020.
[5] K. Giritli Nygren and A. Olofsson, “Managing the Covid-19 pandemic through individual responsibility: the consequences of a world risk society and enhanced ethopolitics,” J. Risk Res., 2020.
[6] S. J. Daniel, “Education and the COVID-19 pandemic,” Prospects, 2020.
[7] C. Dewey, S. Hingle, E. Goelz, and M. Linzer, “Supporting Clinicians During the COVID-19 Pandemic,” Ann. Intern. Med., 2020.
[8] L. Rampal and L. B. Seng, “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic,” Medical Journal of Malaysia, vol. 75, no. 2. 2020.
[9] “‘Corridor care’: the new normal,” Nurs. Manage., vol. 27, no. 1, 2020.
[10] O. Nash, “Problem solving,” in Basic Concepts in Family Therapy: An Introductory Text, Second Edition, 2014.
[11] S. Greiff, D. V. Holt, and J. Funke, “Perspectives on problem solving in educational assessment: Analytical, interactive, and collaborative problem solving,” J. Probl. Solving, vol. 5, no. 2, 2013.
[12] H. Lau et al., “The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China,” J. Travel Med., 2020.
[13] S. K. Kar, S. M. Y. Arafat, P. Sharma, A. Dixit, M. Marthoenis, and
86 | New Normal, Kajian Multidisiplin
R. Kabir, “COVID-19 pandemic and addiction: Current problems and future concerns,” Asian Journal of Psychiatry, vol. 51. 2020.
[14] F. Di Gennaro et al., “Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: A narrative review,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no. 8. 2020.
[15] B. Pfefferbaum and C. S. North, “Mental Health and the Covid-19 Pandemic,” N. Engl. J. Med., 2020.
[16] Ö. Açikgöz and A. Günay, “The early impact of the Covid-19 pandemic on the global and Turkish economy,” Turkish J. Med. Sci., vol. 50, no. SI-1, 2020.
[17] “Adapting to a new normal,” C&EN Glob. Enterp., vol. 98, no. 13, 2020.
[18] “Analysis of Mathematical Problem Solving Ability Based on Student Learning Stages Polya on Selective Problem Solving Model,” Unnes J. Math. Educ., vol. 6, no. 1, 2017.
[19] N. E. Zakiah, Y. Sunaryo, and A. Amam, “Implementasi Pendekatan Kontekstual Pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berdasarkan Langkah-Langkah Polya,” Teorema Teor. dan Ris. Mat., vol. 4, no. 2, 2019.
[20] T. C. Lau and D. C. Y. Ng, “Online Food Delivery Services : Making Food Delivery the New Normal,” J. Mark. Adv. Pract., vol. 1, no. 1, 2019.
[21] A. M. Aziz and motorplus-online.com, “Dampak Virus Corona Meluas, Driver Ojek Online Gelisah Dapur ‘Tidak Ngebul ‘,” www.motorplus-online.com, 2020. .
[22] K. A. Eddleston, E. R. Banalieva, and A. Verbeke, “The Bribery Paradox in Transition Economies and the Enactment of ‘New Normal’ Business Environments,” J. Manag. Stud., vol. 57, no. 3, 2020.
[23] D. Ahlstrom, J. L. Arregle, M. A. Hitt, G. Qian, X. Ma, and D. Faems, “Managing Technological, Sociopolitical, and Institutional Change in the New Normal,” J. Manag. Stud., vol. 57, no. 3, 2020.
[24] C. Dziuban, C. R. Graham, P. D. Moskal, A. Norberg, and N. Sicilia, “Blended learning: the new normal and emerging technologies,” Int. J. Educ. Technol. High. Educ., vol. 15, no. 1, 2018.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 87
Bab 7
Peningkatan Akurasi Tes Daring Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar di Masa Pandemi Covid-19 Bulkani7
Pengantar
Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan tatanan sosial, termasuk di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, keadaan pandemi Covid-19 memaksa penyesuaian sistem pendidikan, baik dari segi perencanaan, proses maupun evaluasi pendidikan. Proses pembelajaran yang semula melalui tatap muka secara langsung, mau tidak mau harus disesuaikan menjadi pembelajaran daring. Perubahan pembelajaran ke sistem daring membawa banyak konsekuensi, menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain (1). Seberapa siap pendidik dan peserta didik melaksanakan proses sistem pembelajaran daring? (2). Bagaimana kualitas sistem pembelajaran daring jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran luring? (3). Bagaimana mengontrol kualitas interaksi pendidik-peserta didik dalam pembelajaran daring? (4). Bagaimana kesiapan infrastruktur pendukung pelaksanaan sistem pembelajaran daring? (5). Bagaimana ketersediaan sinyal internet di berbagai daerah? (6). Bagaimana menilai hasil belajar peserta didik dalam sistem pembelajaran daring? Beberapa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar yang sering diperdebatkan para pendidik.
Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran adalah evaluasi hasil belajar. Dalam pengertian yang sempit, Evaluasi hasil belajar dapat diartikan sebagai upaya menilai perubahan perilaku sebagai capaian dari proses pembelajaran [1], dikaatakan juga makna evaluasi sebagai upaya untuk mengambil keputusan dari suatu proses penilaian [2]. Dalam konteks pembelajaran, maka dari kegiatan evaluasi, kita dapat mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Melakukan evaluasi pada dasarnya adalah membandingkan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai menggunakan teknik dan alat tertentu. Evaluasi tersebut melalui dua tahapan, yakni mengukur dan menilai. Mengukur memiliki makna sebagai kegiatan membandingkan antara capaian obyek pengukuran dengan suatu standar atau patokan tertentu. Sedangkan menilai bermakna melakukan interpretasi atau mengolah hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran diperoleh skor hasil
7 Dr. Bulkani, M.Pd, Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
88 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pengukuran, sedangkan dari penilaian diperoleh nilai. Dengan demikian, proses penilaian juga dapat dimaknai sebagai kegiatan merubah skor menjadi nilai.
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar terdiri dari dua jenis. Secara umum dibedakan menjadi teknik tes dan non tes. Penggunaan masing-masing teknik ini disesuaikan dengan ranah hasil belajar yang akan diukur. Berdasarkan taksonomi Bloom, hasil belajar dibedakan menjadi hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Perbedaan ranah hasil belajar ini menyebabkan perbadaan teknik dan instrumen yang digunakan. Untuk mengukur hasil belajar ranah kognitif, umumnya digunakan teknik tes, dengan berbagai bentuk atau jenis tes. Hasil belajar ranah afektif diukur menggunakan teknik non tes seperti kuisioner, wawancara, observasi, dan semacamnya. Sedang-kan untuk mengukur hasil belajar ranah psikomotor, digunakan teknik tes kinerja atau tes perbuatan. Dalam masa pandemi Covid-19, berbagai teknik pengukuran hasil belajar tersebut cenderung digunakan secara daring.
Tes daring sebenarnya mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an, yakni dengan dikembangkannya tes psikologi berbasis internet, yang kemudian berkembang menjadi testing bidang-bidang lainnya [1]. Tes daring ini kemudian berkembang dalam area pengukuran psikologis yang lebih luas, antara lain dalam bidang pengukuran hasil belajar. Pengukuran hasil belajar merupakan salah satu upaya untuk meng-evaluasi proses pembelajaran daring, selain dimensi-dimensi yang lain. Evaluasi dikatakan juga sebagai sistem pembelajaran daring semestinya tidak hanya memuat dimensi proses dan hasil belajar, tetapi juga menilai dimensi lingkungan belajar peserta didik, termasuk pada saat mengerjakan soal tes [4].
Dalam pengukuran hasil belajar, umumnya para pendidik menggunakan instrumen berupa tes yang bersifat daring juga. Dari respon peserta didik terhadap tes itu, pendidik memperoleh skor yang kemudian diolah menjadi nilai. Nilai ini melambangkan capaian hasil belajar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berbeda dengan model evaluasi luring yang umumnya dipakai saat belum terjadi pandemi, maka model evaluasi daring menyebabkan menurunnya tingkat keyakinan terhadap hasil pengukuran. Penyebabnya antara lain adalah lemahnya pengawasan. Dalam hal ini pengukur (pendidik) tidak mendapat keyakinan kuat bahwa obyek ukur (peserta didik) mengerjakan perintah instrumen secara mandiri tanpa bantuan orang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 89
lain dalam batas waktu yang telah ditentukan. Padahal, capaian hasil belajar seseorang dilambangkan dengan menyelesaikan tugas belajarnya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, penggunaan instrumen pengukuran secara daring tidak dapat dihindari sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Tes hasil belajar yang digunakan secara daring memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan tes daring adalah daya jangkaunya yang luas dengan standar yang sama untuk setiap peserta tes. Tes ini mampu melakukan pengukuran pada populasi yang luas pada saat bersamaan. Pembelajaran dan tes daring bisa menekan biaya sehingga memungkinkan sistem pendidikan global [5]. Tes daring Tes daring juga mampu meminimalkan kesalahan administrasi pelak-sanaan tes dan cenderung tidak terpengaruh oleh karakteristik peserta tes di luar substansi yang diukur, seperti keindahan tulisan tangan. Sedangkan kelemahannya antara lain kesulitan mengontrol kondisi lingkungan tes dan pengadministrasian hardware dan software yang menyebabkan waktu terbuang percuma, dan penggunaan layar kom-puter yang mungkin membuat mata cepat lelah [2]. Kesulitan mengontrol lingkungan tes menyebabkan menurunnya keyakinan pengukur ter-hadap hasil pengukuran.
Peningkatan keyakinan terhadap hasil pengukuran secara daring dapat dilakukan melalui beberapa cara. Melakukan pengukuran beberapa kali adalah salah satu solusi untuk mengejar tingkat reliabilitas hasil pengukuran. Dengan melihat konsistensi hasil dari beberapa kali pengukuran, dapat diperoleh gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Selain itu, variasi jenis tes yang digunakan, dapat membantu memberikan gambaran lebih jelas tentang hasil belajar yang dicapai peserta didik. Cara lain yang dapat ditempuh oleh pengukur adalah membuat instrumen baku dengan tingkat kehandalan yang tinggi. Instrumen yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi misalnya, cenderung mampu memberikan gambaran sebenarnya dari capaian hasil belajar peserta didik.
Masalah utama dalam dunia pengukuran hasil belajar adalah akurasi hasil pengukuran tersebut. Pertanyaan mendasar yang selalu timbul pada saat kita memperoleh suatu skor hasil hasil pengukuran adalah, seberapa akurat skor hasil pengukuran yang kita peroleh tersebut mampu menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik? Apakah skor hasil pengukuran yang kita peroleh, sudah meng-
90 | New Normal, Kajian Multidisiplin
gambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik? Apakah terjadi pembiasan pada skor hasil pengukuran itu? Apakah skor hasil pengukuran tersebut masih mengandung unsur kekeliruan (error)? Bagaimana cara meningkatkan akurasi hasil pengukuran tersebut? Dalam konteks tes secara daring, pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana cara pengukur meningkatkan keyakinan bahwa tes yang diberikan tersebut mampu memberikan gambaran yang utuh dan obyektif tentang hasil belajar yang dicapai peserta didik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab dalam tulisan ini.
Pembahasan
Pengukuran hasil belajar sebagai pengukuran tidak langsung
Pengukuran hasil belajar termasuk ke dalam pengukuran tidak langsung. Artinya, kita sebagai pengukur tidak dapat mengukur obyek ukur secara langsung, karena yang dapat kita ukur hanya gejalanya saja. Pada pengukuran tidak langsung, pengukur hanya dapat mengukur gejala atau respon dari obyek yang diukur, kemudian memberi skor pada respon tersebut. Dalam hal ini, pengukur tidak memperoleh keputusan yang eksak tentang hasil pengukurannya, karena skor yang didapat hanya berdasarkan gejala yang timbul setelah diberi stimulus tertentu. Berbeda dengan pengukuran langsung yang mana pengukur dapat mengukur ukuran-ukuran yang diinginkan dari obyek ukur secara langsung. Misalnya pada saat kita mengukur panjang sebuah meja menggunakan meteran, maka kita melakukan pengukuran langsung karena ukuran-ukuran yang ingin kita ukur, dapat langsung dilihat dari satuan-satuan pada meteran yang kita gunakan.
Skor hasil pengukuran tidak langsung masih mengandung ketidakpastian atau kesalahan. Skor hasil pengukuran pendidikan masih bersifat probalistik karena mengandung unsur kekeliruan [7]. Dengan kata lain, skor hasil pengukuran pendidikan, termasuk skor tes hasil belajar, terdiri dari skor sebenarnya (True score) dan skor kekeliruan (Error), yang dapat dilambangkan dalam persamaan berikut :
X = T + Ɛ X = skor hasil pengukuran T = True atau skor sebenarnya Ɛ = Error
Dengan demikian, jika seorang peserta didik memperoleh skor 70 dari hasil sebuah tes hasil belajar, maka skor 70 tersebut belum tentu
New Normal, Kajian Multidisiplin | 91
menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Banyak kombinasi skor T dan Ɛ yang mungkin terjadi, misalnya : 70 = 60 + 10……………………..(1) 70 = 90 + (-20) ………………….(2). Pada persamaan (1) di atas, kemampuan sebenarnya dari peserta didik adalah 60, tetapi karena terdapat skor kekeliruan sebesar 10 maka skor yang diperoleh peserta didik atau skor hasil pengamatannya adalah 70. Kemungkinan berbeda terjadi pada persamaan (2), yang mana kemampuan sebenarnya dari peserta didik adalah 90, tetapi karena terdapat skor kekeliruan sebesar -20 maka skor yang diperoleh peserta didik atau skor hasil pengamatannya adalah 70. Ini berarti, pada sebuah skor yang kita peroleh dari tes hasil belajar misalnya, terdapat tak terhingga banyaknya kemungkinan pasangan skor T dan skor Ɛ.
Dalam pengukuran hasil belajar, tantangan utama pengukur adalah meminimalkan skor kekeliruan atau error. Jika diusahakan skor kekeliruan atau error mendekati nol (Ɛ≈0), maka persamaan X = T + Ɛ akan mendekati X = T + 0, sehingga skor hasil pengamatan akan hampir sama dengan angka true skor. Dengan kata lain, jika dapat diusahakan Ɛ≈0, maka akan terjadi skor hasil amatan mendekati true skor, atau X≈T. Artinya, dengan mengusahakan skor kekeliruan yang sekecil mungkin, maka skor hasil pengamatan yang kita peroleh akan mampu menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Masalahnya adalah, skor X adalah hasil pengamatan, sehingga dapat kita amati skornya. Sedangkan skor T dan Ɛ tidak dapat kita amati, tetapi secara teoretis dapat dikendalikan.
Pada pengukuran hasil belajar model daring, kita bahkan lebih sulit mengendalikan kekeliruan atau error (Ɛ) ini. Unsur Ɛ sebagai bagian dari skor hasil pengamatan X, cenderung meningkat karena tidak adanya pengawasan. Bisa saja adanya campur tangan pihak lain yang membantu pengerjaan jawaban peserta didik, sehingga menyebabkan nilai Ɛ semakin besar sehingga skor hasil amatan semakin jauh dari kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Skor hasil amatan X cenderung membias dari skor true (T), karena banyaknya faktor yang mengotori hasil pengukuran.
Salah satu cara memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukuran hasil belajar secara daring adalah mengupayakan instrumen yang handal dan memenuhi standar, serta berusaha melakukan proses pengukurannya secara benar. Beberapa hal itulah yang akan dibahas dalam bagian berikut ini.
92 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Menggunakan tes lisan secara daring
Salah satu kelemahan tes hasil belajar model daring, khususnya jenis tes tertulis, adalah lemahnya pengawasan sehingga pengukur tidak memiliki keyakinan kuat bahwa tes itu dikerjakan sendiri oleh peserta didik. Tes tertulis yang sifatnya massal atau dikerjakan secara bersamaan oleh banyak peserta didik, menyebabkan lemahnya pengawasan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan tes lisan secara daring.
Tes lisan adalah tes yang perintahnya diberikan secara lisan dan dijawab juga secara lisan oleh peserta didik, mirip dengan wawancara. Perbedaan mendasar antara tes lisan dengan wawancara adalah sama dengan perbedaan antara tes dengan non tes. Meskipun menggunakan interaksi secara lisan, tes lisan berbeda dengan wawancara karena tes lisan digunakan unuk mengukur aspek-aspek hasil belajar kognitif, sedangkan wawancara digunakan untuk mengukur aspek-aspek afektif. Ditinjau dari pola responnya, jawaban dari suatu tes mengandung nilai probabilitas benar atau salah, sedangkan jawaban wawancara selalu bernilai benar. Sering kita mendengar kekeliruan dalam penggunaan istilah tes wawancara, padahal wawancara bukanlah bagian dari tes.
Dalam konteks pelaksanaan tes secara daring, tes lisan dapat diberikan secara perorangan oleh pengukur ke peserta didik secara face to face, atau dapat pula pertanyaan diberikan kepada semua peserta tes secara acak seperti kompetisi. Jika diberikan secara face to face, maka tes lisan secara daring membutuhkan waktu yang cukup lama agar semua peserta tes dapat diukur kemampuannya. Untuk panjang tes atau jumlah butir pertanyaan yang cukup banyak karena luasnya capaian hasil belajar yang ingin diukur, maka model ini kurang memungkinkan digunakan secara daring. Alternatif lain, pengukur menggunakan model tes lisan yang kompetitif dimana peserta tes diberikan pertanyaan secara lisan, kemudian dalam waktu yang dibatasi, peserta tes saling mendahului dan berlomba dalam memberikan jawaban. Model kedua ini relatif tidak memakan waktu yang banyak, akan tetapi azas keadilan dan kesempatan dapat terkurangi karena berbagai faktor seperti kekuatan sinyal internet yang berbeda-beda.
Kelebihan tes lisan yang diberikan secara daring antara lain adalah respon atau jawaban peserta tes terhadap pertanyaan-pertanyaan dapat langsung diperoleh untuk diberikan skor. Pola stumulus-respon yang berlangsung lebih cepat, juga secara face to face, dapat meningkatkan keyakinan pengukur tentang akurasi hasil pengukuran.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 93
Kelebihan lain adalah bahwa tes ini bisa diberikan benar-benar secara daring tanpa adanya interaksi fisik antara pengukur dan peserta tes. Di sisi lain, model tes ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain bahwa tes ini hanya cocok digunakan untuk mengukur capaian hasil belajar yang bersifat ingatan atau pemahaman. Untuk butir-butir pertanyaan yang membutuhkan jawaban analitik dan capaian hasil belajar kognitif yang lebih rumit, maka tes lisan kurang cocok untuk digunakan, karena membutuhkan waktu untuk pengerjaannya maupun untuk menyampaikan jawabannya. Contohnya adalah soal-soal yang jawabannya membutuhkan perhitungan.
Dalam penggunaannya, tes lisan secara daring, harus memper-hatikan aspek-aspek kesiapan psikologis peserta tes. Tidak semua peserta tes siap secara psikologis jika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan lisan dari pengukur atau penguji, apalagi dengan waktu yang dibatasi. Kadangkala jawaban yang diberikan terburu-buru karena merasa dibatasi waktu dan berkompetisi dengan kawan-kawannya yang lain. Jika pertanyaan lisan itu membuat rasa gugup, maka hasil pengukurannya akan mengalami pembiasan. Selain itu, tidak semua peserta tes mampu mengutarakan kalimat yang baik dalam berkomunikasi secara lisan. Kekurangmampuan berkomunikasi dan menyusun kalimat dengan benar, dapat menyebabkan pembiasan hasil pengukuran. Beberapa kelemahan itu dapat menyebabkan inkonsistensi hasil pengukuran, parameter pengotor yang mestinya dihindari dalam pengukuran hasil belajar.
Agar tes lisan yang diberikan secara daring dapat berfungsi dengan baik sebagai alat ukur hasil belajar, maka pengukur harus menempuh beberapa cara, antara lain berupaya menciptakan suasana pengukuran yang menyenangkan, santai, dan tidak intimidatif. Selain itu, cara pemberian tes lisan yang berulang-ulang, dapat membantu peserta tes menjadi terbiasa sehingga tidak menciptakan interaksi yang menegangkan. Tes lisan yang diberikan secara berulang-ulang juga membantu pengukur melihat tingkat konsistensi hasil pengukuran. Kecenderungan konsistensi itu menggambarkan tingkat akurasi instrumen maupun proses pengukuran.
Menggunakan tes parsial berbatas waktu
Proses tes harus berbatas waktu. Batas waktu dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan sehingga mengurangi pembiasan. Hal ini sesuai dengan definisi dari hasil belajar, yakni kemampuan seorang peserta didik menyelesaikan tugas belajarnya dalam satuan
94 | New Normal, Kajian Multidisiplin
waktu tertentu. Pembatasan waktu tes juga memperkecil peluang peserta tes bekerjasama dengan orang lain. Meskipun demikian, batas waktu tersebut harus memperhatikan pula karakteristik peserta tes, karakteristik butir tes, kedalaman materi yang diukur, serta jenis tes yang digunakan. Untuk tes yang bertujuan mengukur kemampuan ingatan dan pemahaman misalnya, waktu yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal tes berbentuk uraian. Tes berbentuk pilihan ganda relatif membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan tes uraian dalam hal pengerjaannya. Demikian pula halnya dengan butir-butir tes yang sukar, akan membutuhkan waktu lebih lama dalam pengerjaannya dibanding dengan butir-butir tes yang mudah.
Tes daring secara parsial yang dimaksudkan adalah, tes tersebut diberikan secara bertahap butir per butir, sehingga peserta tes juga menjawabnya dari butir ke butir. Pengukur pada awalnya bisa membacakan petunjuk dan aturan main pelaksanaan tes, lalu membaca-kan atau menyampaikan secara daring butir soal satu demi satu. Setelah soal nomor pertama dibacakan atau disampaikan, peserta tes langsung mengerjakan dan menjawab soal tersebut secara daring pula hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian seterusnya, butir soal nomor dua segera disampaikan oleh pengukur setelah habisnya batas waktu untuk mengerjakan soal nomor satu. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, cara peserta tes menjawab pun dapat divariasikan. Peserta tes dapat menjawab satu persatu soal tes dan mengirimkannya langsung kepada pengukur, misalnya melalui pesan SMS atau WahtApss. Waktu penyampaian jawaban juga tercatat dengan baik dalam sistem tersebut. Cara lainnya adalah, jawaban peserta didik disiapkan dalam format aplikasi di sistem google, misalnya peserta tes langsung menandai pilihan alternatif jawaban pada program bit.ly yang sudah disiapkan pengukur. Model ini lebih memudahkan pengukur untuk memberikan skor secara otomatis.
Model tes daring secara parsial ini memberikan beberapa keunggulan, antara lain bahwa obyektivitas dan keadilan relatif dapat ditingkatkan dibanding menggunakan tes tertulis daring yang konven-sional. Pada tes daring yang konvensional, peserta didik menjawab soal tes yang diberikan dalam bentuk perangkat tes. Artinya, terdapat sekumpulan butir tes yang harus dijawab peserta tes dalam batas waktu tertentu, sehingga peserta tes bisa menjawab secara berurutan, memilih soal yang dianggapnya mudah, atau mengulangi kembali untuk
New Normal, Kajian Multidisiplin | 95
menjawab butir tes yang pada awalnya terlewatkan. Cara ini memberikan kesempatan kepada peserta tes untuk memperoleh skor lebih besar jika waktunya mencukupi. Padahal, mestinya setiap butir tes mengukur aspek perilaku hasil belajar yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan batas waktu yang berbeda pula untuk mengerjakannya. Hakikatnya, pengukur memberikan jumlah waktu yang lebih banyak kepada peserta tes yang memiliki kemampuan lebih baik, sehingga ada ketidakadilan.
Model tes daring yang digunakan secara parsial butir per butir ini tentu juga punya kelemahan, antara lain bahwa peserta didik dapat tergesa-gesa dalam menjawab setiap butir tes. Peserta tes akan merasa diburu waktu sehingga dirasakannya memiliki kesempatan semakin kecil untuk menjawab benar. Perasaan kurang tenang dan cemas ini dapat menyebabkan pembiasan dalam hasil pengukuran. Kecemasan pada peserta tes cenderung akan menghasilkan skor hasil tes yang under estimate [8}. Selain itu, peserta tes juga dapat mengalami kelelahan, sehingga kemampuannya menurun pada saat mengerjakan soal-soal di bagian akhir tes. Kelemahan yang terakhir ini dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan secara silang butir-butir soal tes yang mengukur kemampuan kognitif pada level tinggi (seperti soal ingatan dan pemahaman) pada dengan butir soal tes yang mengukur kemampuan yang lebih kompleks.
Melakukan tes berulang
Melakukan pengukuran secara berulang-ulang terhadap obyek ukur yang sama, dapat meningkatkan akurasi pengukuran. Pengukuran berulang menggunakan instrumen yang sama secara substantif, akan mendekatkan skor hasil amatan X dengan skor T yang menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Hal ini didasari pada asumsi bahwa kemampuan atau penguasaan seseorang terhadap bahan ajar tertentu adalah konstan, sekalipun diukur dengan berbagai alat ukur dan beberapa kali pengukuran. Dengan kata lain, dalam persamaan X = T + Ɛ, ada kecenderungan berlaku Xi = T + Ɛi, sehingga sampai dengan pengukuran yang ke-i sekalipun, skor T tidak akan berubah. Perubahan skor amatan Xi pada akhirnya hanya tergantung dari atau berkorelasi dengan besaran skor kekeliruan Ɛi. Dalam bentuk persamaan, hal itu dapat dinyatakan sebagai berikut :
X1 = T + Ɛ1 X2 = T + Ɛ2
Xi = T + Ɛi
96 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Menurut Naga [3] skor kekeliruan terjadi secara acak, bisa
menyebabkan penambahan maupun pengurangan pada skor amatan. Dengan demikian, untuk jumlah pengulangan tes yang banyaknya tak terhingga (i ∞), maka rata-rata skor kekeliruan Ɛ akan mendekati 0 (ditulis µƐ≈0). Dengan kata lain, untuk jumlah tes yang dilakukan berulang-ulang, maka berlaku µX≈T karena µƐ≈0. Artinya, rata-rata skor amatan X mendekati angka true skor T, jika dilakukan tes yang berulang-ulang. Walaupun pada kenyataannya, adalah tidak mungkin kita memberikan pengulangan tes sebanyak tak terhingga kepada peserta didik, karena berbagai keterbatasan. Namun berbagai keter-batasan yang dimiliki oleh tes sebagai alat ukur hasil belajar, dapat diatasi dengan melakukan pengukuran secara kontinyu dan berulang [9].
Pengulangan pada tes daring untuk mengukur hasil belajar, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengukur menyusun dua atau beberapa perangkat tes dengan jenis dan materi tes yang sama. Dengan cara ini, peserta didik diberikan tes dengan jenis yang sama (misalkan jenis tes pilihan ganda), dengan bunyi pertanyaan yang berbeda, tetapi tetap mengukur penguasaan terhadap materi yang sama. Kedua tes tersebut diusahakan diberikan pada waktu berbeda dengan tenggang waktu yang cukup. Kedua, pengukur menggunakan beberapa jenis dan bentuk tes berbeda, tetapi dengan substansi materi tes yang sama. Misalkan kita akan mengukur capaian hasil belajar mata kuliah Metodologi Penelitian, maka kita dapat membuat tes berbentuk pilihan ganda, uraian, isian, dan menjodohkan. Hasil dari beberapa tes ini kemudian dicari skor rata-ratanya untuk setiap peserta didik. Rata-rata skor itulah yang mendekati gambaran kemampuan sebenarnya tentang capaian hasil belajar peserta didik. Pada saat ini, terdapat beberapa pilihan software berbasis daring untuk membuat butir-butir soal yang bisa dijawab juga secara daring. Model tes daring menggunakan software ini bahkan lebih memudahkan pengukur dalam memberikan skor secara otomatis.
Cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan pengulangan pengukuran, adalah melakukan tes daring segera setelah suatu pokok bahasan selesai dibahas. Evaluasi ini sering dinamakan juga evaluasi formatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada bagian-bagian tertentu, yang dapat diguna-kan sebagai umpan balik bagi perubahan strategi pembelajaran [9]. Pendekatan formatif dapat digunakan atas asumsi bahwa bahan ajar
New Normal, Kajian Multidisiplin | 97
yang diberikan kepada peserta didik merupakan satu kesatuan utuh sekalipun terbagi ke dalam beberapa pokok bahasan. Sehingga, capaian dan penguasaan terhadap masing-masing pokok bahasan juga melambangkan capaian hasil belajar peserta didik terhadap keseluruhan bahan ajar. Dengan pendekatan ini, maka skor hasil belajjar peserta didik dapat diwakili oleh skor rata-rata dari skor yang diperoleh untuk setiap pokok bahasan. Tes formatif bukan hanya dimaksudkan untuk mengukur capaian hasil belajar, tapi juga unuk mengukur kualitas proses pembelajaran, karena hasil tes formatif pada pokok bahasan tertentu dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran tahap berikutnya [10].
Untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap beberapa hasil tes berulang, kita dapat melakukan pengecekan koefisien korelasi antara hasil suatu tes dengan hasil tes lainnya. Saat ini banyak cara mudah dan praktis untuk menghitung koefisien korelasi, antara lain menggunakan program Microsoft Excell yang sudah sangat umum dipakai di Indonesia. Koefisien korelasi antara skor hasil suatu tes dengan hasil tes lainnya melambangkan konsistensi hasil pengukuran. Konsistensi ini disebut sebagai koefisien reliabilitas hasil pengukuran. Dengan menghitung koefisien korelasi antara skor hasil suatu tes dengan hasil tes lainnya, pada dasarnya kita beruapaya menggetahui konsisten atau reliabel tidaknya hasil pengukuran tersebut. Koefisien korelasi antar hasil tes tersebut dianggap cukup memadai jika berada pada kisaran 0,75 ≤ ρxx ≤ 1,00. Koefisien reliabilitas untuk pengukuran pada beberapa cabang ilmu, masih bisa mentoleransi koefisien sebesar ρxx = 0,50, walaupun pada umumnya banyak pengukur yang mematok koefisien minimal sebesar ρxx = 0,75 [11].
Memperpanjang tes
Memperpanjang tes di sini diartikan sebagai menambah jumlah butir tes dalam jumlah yang cukup, dengan memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan tes. Dalam banyak literatur ilmu pengukuran hasil belajar, menambah jumlah butir tes, dapat mening-katkan koefisien reliabilitas tes tersebut. Pada umumnya menambah panjang tes akan meningkatkan reliabilitas [8]. Sedangkan [4], berpen-dapat bahwa penambahan jumlah butir tes yang berkualitas adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan koefisien reliabilitas, yang digambarkan melalui tabel hasil ujicobanya sebagai berikut :
98 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tabel: Hubungan panjang tes dengan reliabilitas pada percobaan Sax
Banyak butir
Variansi true skor (δ2T)
Variansi skor amatan (δ2x)
Skor keliru (Ɛ)
Reliabilitas
25 20 40 20 0.50 50 80 120 40 0.67
100 320 400 80 0.80
Sumber : [4] Dari tabel di atas tampak bahwa penambahan panjang tes, yakni
dengan menambah butir-butir soal yang berkualitas, akan menyebabkan peningkatan koefisien reliabilitas tes tersebut. Sebagaimana juga asumsi yang mendasari pengukuran berulang, maka penambahan butir soal tes menyebabkan variansi skor amatan X akan semakin mendekati variansi skor true, atau ditulis δ2x ≈ δ2T. Sehingga, rasio δ2x terhadap δ2T juga akan semakin besar. Rasio antara variansi true skor δ2T terhadap variansi skor amatan δ2x merupakan koefisien reliabilitas, atau ditulis ρxx = δ2T / δ2x dimana δ2x = δ2T + Ɛ
Untuk menambah keyakinan tentang peningkatan reliabilitas, maka butir soal tes yang ditambahkan harus sama kualitasnya dengan kualitas butir soal sebelumnya. Yang dimaksud dengan butir-butir soal berkualitas adalah butir-butir soal tes yang memiliki tingkat validitas isi yang tinggi. Validitas isi, atau content validity, adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat akurasi atau keabsahan butir-butir tes dari segi materi tes. Suatu butir tes disebut memiliki validitas isi, jika butir-butir tes tersebut berisi pertanyaan atau perintah yang sesuai dengan materi atau substansi kompetensi atau perilaku hasil belajar yang ingin diukur. Jika kita ingin mengukur kompetensi peserta didik tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama misalnya, maka butir-butir yang valid secara isi adalah butir-butir tes yang menanyakan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jika terdapat butir soal tes yang mena-nyakan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, maka butir tersebut bukanlah butir tes yang valid secara isi.
Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti tentang banyaknya butir soal yang ideal sehingga dicapai koefisien reliabilitas tes tersebut. Pertimbangan teoretis maupun praktis dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan banyaknya butir tes. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, secara teoretis seharusnya capaian perilaku hasil belajar diukur menggunakan tak terhingga banyaknya butir tes. Akan tetapi secara praktis, banyak butir tes tergantung dari jenis tes, keluasan materi, tingkat kesukaran butir tes, dan waktu yang tersedia. 20 butir untuk soal pilihan ganda terlalu sedikit untuk soal jenis pilihan ganda
New Normal, Kajian Multidisiplin | 99
atau benar salah, tetapi menjadi terlalu banyak untuk butir tes berbentuk uraian. Keputusan tentang panjang tes akhirnya didasarkan pada pengalaman penguku [9]r.
Menggunakan hasil tes lain sebagai kriterium
Dalam dunia pengukuran pendidikan dikenal istilah validitas kriterium. Seperangkat alat tes disebut memiliki validitas kriterium jika hasil pengukuran menggunakan perangkat tes tersebut memiliki korelasi positif dengan sebuah kriteria yang sudah dipercaya akurasinya. Suatu butir tes dikatakan memiliki validitas kriterium jika memiliki kesesuaian atau kesejajaran dengan kriteria tertentu. [10] Sedangkan [5] menyatakan bahwa validitas kriterium yang disebut juga sebagai concurrent validity, menekankan pada keseuaian antara hasil suatu tes dengan catatan tentang pengalaman yang telah diperoleh peserta didik. Kesesuaian antara hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan kriteriumnya harus diambil datanya dari kelompok yang sama [14].
Sebagai kriterium, kita dapat gunakan hasil-hasil tes sebelumnya, yang telah mengukur hal yang sama atau relevan, dan diyakini telah terstandar dan telah menggambarkan kemampuan sebenarnya dari peserta tes. Selain itu, hasil observasi dan pengalaman empirik dari pendidik juga dapat digunakan sebagai kriterium. Sebagai pendidik, pada umumnya kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik dalam bidang yang kita ajarkan. Gambaran tentang karakteristik itu secara kualitatif dapat digunakan sebagai kriterium untuk menguji akurasi hasil tes daring yang kita gunakan. Tes yang baik, umumnya dapat dikerjakan secara baik pula oleh kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi (sering disebut sebagai kelompok upper), dan cenderung tidak bisa dikerjakan oleh peserta didik yang memiliki kemampuan rendah (kelompok lower). Dalam dunia pengukuran pendidikan, kemampuan butir tes untuk membedakan kelompok upper dan lower ini disebut daya pembeda butir tes.
Untuk mengetahui akurasi hasil tes daring dengan pendekatan kuantitatif, pengukur dapat mencari koefisien korelasi antara skor hasil tes daring tersebut dengan skor tertentu yang telah ditetapkan sebagai kriterium. Saat ini, perhitungan koefisien korelasi antara dua jenis skor, misal skor X dengan skor Y, dengan mudah dapat dilakukan melalui program Microsoft Excell, SPSS maupun software lainnya yang sudah umum di pasaran. Koefisien korelasi yang tinggi, melambangkan bahwa tes daring yang disusun dan digunakan pengukur, telah memiliki
100 | New Normal, Kajian Multidisiplin
akurasi yang tinggi pula. Dalam konteks ini, pengukur tidak semestinya puas dengan koefisien korelasi yang signifikan antara skor hasil tes daring dengan skor hasil tes yang dijadikan kriterium. Jika meng-gunakan pendekatan statistika, suatu koefsien korelasi akan signifikan keberlakukannya pada populasi jika koefisien hubungan antara X dengan Y (ditulis rxy) lebih besar dari nilai r tabel, sedangkan r tabel besarannya tergantung dari besaran sampel. Sebagai misal, untuk besaran sampel n=70 dan taraf signifikansi 5%, diperoleh bahwa rxy = 0,25 sudah cukup signifikan. Perlu diingat bahwa, pengujian korelasi dengan uji statistika parametrik, hanya melambangkan ada tidaknya korelasi tersebut pada populasi. Sedangkan kualitas hubungan itu tergambar dari besaran koefisien korelasi rxy. Artinya, untuk mengetahui tingkat akurasi hasil tes daring yang kita gunakan, kita tidak boleh puas dan berhenti pada pengujian signifikansi semata, tetapi lebih fokus pada besaran koefisien korelasi tersebut. Umumnya, koefisien korelasi rxy > 0,70 sudah dianggap bagus kualitas hubungannya. Azwar [6] bahkan menyarankan untuk menyertakan pertimbangan-pertimbangan rasio-nal-kualitatif dalam menentukan tingkat akurasi hasil tes menggunakan pendekatan kriterium.
Membuat butir tes dengan tingkat kesukaran sedang
Tingkat kesukaran butir tes dilambangkan oleh kualitas respon peserta tes terhadap butir soal tersebut. Suatu butir soal disebut sukar jika sebagian besar peserta tes tidak bisa menjawab pertanyaan pada soal tersebut. Tingkat kesukaran butir melambangkan proporsi peserta tes yang menjawab benar suatu butir tes. Sebaliknya disebut mudah jika sebagian besar peserta tes mampu menjawabnya. Ditinjau dari batasan tersebut, maka tingkat kesukaran butir tes akan tergantung pada karakteristik peserta tes. Artinya, suatu butir soal tes yang dianggap sukar oleh sekelompok peserta tes dengan kemampuan akademik yang rendah (kelompok lower), bisa jadi akan dianggap mudah oleh kelompok peserta tes yang memiliki kemampuan yang tinggi (kelompok upper). Ini menandakan bahwa ada kemungkinan karakteristik butir tes akan berubah sejalan dengan perubahan karakteristik peserta tes, atau sebaliknya.
Tingkat kesukaran butir tes merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi hasil tes. Komponen skor kekeliruan Ɛ akan cenderung meningkat pada butir-butir tes yang sangat sukar atau sangat mudah. Pada butir-butir yang sangat sukar, peserta tes cenderung tidak bisa menjawab atau mengerjakan soal tes tersebut.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 101
Sebaliknya pada butir-butir soal tes yang mudah, peserta tes akan cenderung bisa mengerjakan soal tersebut. Kedua fenomena ini mengakibatkan kecenderungan keseragaman respon atau jawaban peserta tes, yakni keseragaman pada skor rendah (untuk butir soal tes yang sukar) atau keseragaman pada skor tinggi (untuk butir tes yang mudah). Hal ini mengakibatkan komponen kekeliruan meningkat, dan menyebabkan koefisiien reliabilitas menurun. Jika ditinjau dari persamaan koefisien reliabilitas ρxx = δ2T / δ2x dimana δ2x = δ2T + Ɛ, maka peningkatan komponen kekeliruan akan meningkatkan variansi δ2x sebagai factor pembagi, sehingga menurunkan nilai koefisien reliabilitas ρxx . Sax [4], berpendapat bahwa butir tes yang terlalu sukar akan cenderung meningkatkan kekeliruan secara acak, dan akan berkon-tribusi bagi penurunan koefisien reliabilitas, sebaiknya menggunakan butir tes dengan tingkat kesukaran antara 0.33 – 0.77 [7].
Butir-butir soal tes yang baik adalah butir soal dengan tingkat kesukaran sedang, atau minimal proporsi soal sedangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan butir soal sukar dan mudah. Komposisi butir soal sukar: sedang: mudah disarankan paling banyak adalah 20%: 50% : 30%. Dalam pandangan pengukuran, akan lebih baik jika semua soal yang digunakan adalah butir soal dengan tingkat kesukaran sedang. Butir soal yang sedang akan cenderung dikerjakan secara benar oleh kelompok upper, dan cenderung akan salah jika dikerjakan oleh kelompok lower. Artinya, butir-butir soal tes dengan tingkat kesukaran sedang cenderung mampu berfungsi sebagai alat ukur yang baik karena mampu membedakan peserta tes kelompok upper dan kelompok lower. Hakekat tujuan pelaksanaan tes adalah membedakan antara peserta tes pada kedua kelompok tersebut, dengan harapan memberi skor hasil tes yang tinggi kepada kelompok upper dan skor rendah pada kelompok lower. Jika terjadi sebaliknya, maka butir tes tersebut tidak mampu berfungsi sebagai alat ukur yang akurat.
Pada penyusunan tes daring, pengukur dapat mempersiapkan butir soal tes dengan tingkat kesukaran sedang melalui tiga cara. Pertama, melakukan prediksi secara kualitatif. Dalam menyusun butir soal, pengukur memperkirakan tingkat kesukaran butir soal berda-sarkan pengalamannya berinteraksi dengan peserta tes. Dalam hal ini, pengukur sudah sangat memahami karakteristik dan kemampuan peserta tes sehingga dapat memprediksi bahwa butir soal tes yang disusun tersebut termasuk dalam tingkat kesukaran sedang. Kedua, menggunakan tes yang sudah diketahui tingkat kesukarannya. Cara ini
102 | New Normal, Kajian Multidisiplin
membutuhkan koleksi soal tes yang sudah terstandar. Pengukur memiliki kumpulan soal tes yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan diukur. Saat ini, banyak butir soal tes yang dapat diakses secara cepat melalui berbagai bank soal. Ketiga, berdasarkan hasil ujicoba. Melalui cara ini, pengukur terlebih dahulu menyusun butir-butir soal tes dengan materi tertentu, kemudian mengujicobakannya kepada kelompok lain yang kemampuannya dianggap setara dengan peserta tes. Dari hasil ujicoba, maka berbagai karakteristik butir tes, termasuk tingkat kesukaran butir, dapat diketahui.
Penutup
Sebagai bagian dari pengukuran tidak langsung, maka pengukuran hasil belajar memerlukan instrumen yang handal dan akurat, terlebih jika instrumen yang digunakan berupa tes daring. Salah satu kelemahan penggunaan tes daring adalah lemahnya pengawasan sehingga pengukur kurang memiliki keyakinan tentang akurasi hasil tes. Pada penggunaan tes tertulis secara daring misalnya, pengawasan ketat secara bersamaan terhadap setiap peserta tes, kurang memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, penggunaan tes secara daring dipengaruhi oleh faktor non psikologis seperti kualitas sinyal internet. Kelemahan tersebut menyebabkan komponen skor kekeliruan semakin meningkat, sehingga menurunkan koefisien reliabilitas tes. Untuk itu dibutuhkan beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pengukur agar tingkat akurasi hasil pengukuran meningkat sehingga mampu menambah keyakinan terhadap hasil belajar yang diukur.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengukur untuk meningkatkan akurasi tes daring sebagai alat ukur hasil belajar peserta didik, diantaranya adalah (1). Merencanakan dan membuat tes dengan baik. Perencanaan pengukuran yang baik akan mampu meningkatkan koefisien reliabilitas tes. (2). Menggunakan tes lisan secara daring. Penggunaan tes lisan secara daring memungkinkan interaksi stimulus-respon seketika sehingga meningkatkan obyektivitas pengukuran dan hasilnya. (3). Melakukan tes berulang. Tes yang dilakukan berulangkali, misalnya setiap akhir pokok bahasan, cenderung mampu menggam-barkan kemampuan sebenarnya dari peserta tes sehingga meningkatkan koefisien reliabilitas (4). Memperpanjang tes. Dari banyak studi, memperpanjang tes dengan cara menambah butir-butir tes yang setara, mampu meningkatkan koefisien reliabilitas tes. Banyak butir tes tergantung dari jenis tes, keluasan materi, tingkat kesukaran, dan waktu yang tersedia, (5). Menggunakan hasil tes lain sebagai kriterium. Cara ini
New Normal, Kajian Multidisiplin | 103
dilakukan dengan mencari relevansi hasil tes daring dengan data atau pengalaman yang telah ada tentang capaian hasil belajar peserta tes. Relevansi tersebut dapat dicari secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan analisis korelasi. (6). Menggunakan butir-butir soal tes dengan tingkat kesukaran sedang. Butir-butir soal tes dengan taraf kesukaran sedang cenderung mampu membedakan antara peserta tes kelompok upper dan kelompok lower, yang secara hakiki merupakan fungsi tes hasil belajar.
Rujukan
[1] Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield, Evaluation, Theory, Models, & Applications, San Francisco: Jossy-Blass A Wimpley Imprint, 2007.
[2] G. Sax, Principles of Educational and Psychological Measurement and Evaluation, San Francisco: Phoenix Publishing Services Inc, 1980.
[3] Azy Barak & Nicole English, "Prospects and Limitations of Psychological Testing on Internet," Journal of Technology in Human Services, vol. 19, no. 2-3, pp. 65-68, 2008.
[4] B. Khan, Web Based Training: a Framework for Web-Based Learning, New Jersey: Englewood Cliffs, 2001.
[5] T. Nguyen, "The Effectiveness of Online Learning: Beyond No Significant Difference and Future Horizons," MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, vol. 11, no. -, p. 310, 2015.
[6] Jan M. Noyes & Kate J. Garland, "Computer vs Paper-Based Tasks: Are They Eqivalent?," Ergonomics, vol. 51, no. -, pp. 1352-1375, 2008.
[7] D. S. Naga, Pengantar Teori Sekor pada Pengukuran Pendidikan, Jakarta: Gunadarma, 1992.
[8] D. Mardapi, Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
[9] S. Azwar, Test Prestasi, Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar, Yogyakarta: Liberty, 1987.
[10] S. E. P. Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
104 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[11] D. S. Naga, Teori Sekor pada Pengukuran Mental, Jakarta: PT Nagasari Citrayasa , 2013.
[12] S. A. Livingston, Test Reliability-Basic Concepts, New Jersey: Educational Testing Service, 2018.
[13] E. F. Aries, Asesmen dan Evaluasi, Malang: Aditya Media Publishin, 2011.
[14] Mansyur, Harun Rasyid, Suratno, Asesmen Pembelajaran di Sekolah, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009.
[15] R. Ebel, Essential of Educational Measurement, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1979.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 105
Bab 8
Kinerja Dosen dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi Covid-19 Heni Sukrisno 8
Pengantar
Indonesia saat ini sedang dilanda bencana, yaitu wabah yang disebut dengan pandemi virus corona yang atau disebut COVI D-19. Wabah ini tidak hanya melanda Indonesia saja tetapi juga melanda seluruh dunia. Jumlah orang terkonfimasi positif terinfeksi virus tersebut hingga saat ini terus bertambah penyebarannya di dunia melebihi dari 150 negara. Hal itu disebabkan oleh belum ditemukan vaksin maupun obat dapat digunakan untuk memhambat atau menghentikan penyebaran virus tersebut. Dampak pandemi tersebut menyebabkan dosen, mahasiswa mengalami kesulitan untuk melaksanakan pem-belajaran secara tatap muka langsung atau Luar jaringan (Luring). Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (Daring). Pembelajaran Daring adalah pembelajaran dengan menggunakan electronik dengan bantuan internet yang disebut dengan e-learning. Selain itu juga berdampak pada kinerja dosen dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi juga mengalami kesulitan untuk dapat dilaksanakan langsung di lapangan.
Pemerintah telah mengambil kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Social distancing. Setiap Orang Diharapkan untuk menjaga jarak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dilarang untuk melakukan kerumunan atau mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, himbauan untuk tinggal di rumah. Kebijakan tersebut akan efektif apabila setiap orang atau warga negara mematuhi himbauan dan larangan-larangan tersebut. Dampak yang lain adalah terhadap perkembangan perekomian, penganguran, dan lain-lain. Seiring dengan hal tersebut saat ini pemerintah juga telah menetapkan suatu kebijakan yang disebut dengan
8 Dr. Heni Sukrisno, M.Pd, Dosen Program Profesi Guru, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya, Surabaya
106 | New Normal, Kajian Multidisiplin
New Normal. Tatanan baru, kebiasaan baru, perilaku baru dalam beradaptasi terhadap Covid-19 ini. New Normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah ternyata juga menimbulkan banyak kecemasan bagi beberapa orang. Kecemasan tersebut antara lain mereka harus melaksanakan protokoler yang telah ditetapkan atau kebiasaan-kebiasan baru. Kecemasan lain adalah dengan dibukanya sektor bisnis, beberapa sekolah, perkantoran yang mengakibatkan bertambahnya orang yang terpapar covid-19. Kecemasan, keresahan disebabkan oleh kekhawatiran sebagian orang akan tertular covid-19 tersebut, sehingga berakibat terjadinya stress, burnout pada diri mereka.
Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tridharma tidak harus berhenti karena adanya wabah ini, bahkan berupaya berdaptasi dan berinovasi dalam penyelenggaraannya. Hal itu dilakukan sebagai kewajiban dalam pelaksanakan Tridharma untuk dipertanggungjawab-kan kepada masyarakat dan pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan mutu pendidikan secara ber-kelanjutan. Perguruan tinggi berupaya untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan walaupun di tengah-tengah wabah covid yang sedang melanda negeri ini. Peningkatan mutu tersebut dengan melakukan perbaikan pada aspek input, proses, output, dan outcome. Perbaikan aspek-aspek tersebut salah satunya adalah dengan mening-katkan kinerja Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Peningkatan kinerja dosen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dosen merupakan ujung tombak dalam melaksanakan proses pem-belajaran di perguruan tinggi. Mengingat dosen mempunyai tugas sebagai pendidikan, dan juga sebagai ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi dengan pendidikan. Hasil Penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan selanjutnya dikembang-kan menjadi suatu artikel ilmiah. Artikel ilmiah tersebut selanjutnya dipublikasikan secara nasional maupun internasional yang bereputasi atau terindeks. Selain itu hasil penelitian dan pengabdian tersebut dapat dikembangkan menjadi buku ajar, buku monograf, referensi maupun bookschapter.
Kinerja Dosen adalah unjuk kerja, hasil kerja dan prestasinya yang dapat ditunjukkan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Unjuk kerja adalah bagaimana seorang dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam merencanakan, melaksanakan, meng-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 107
evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih mahasiswa. Hasil kerja adalah bagaimana seorang dosen mampu menunjukkan bahwa kom-petensi mahasiswa setelah proses pembelajaran melebihi standar yang telah ditentukan. Di samping itu hasil kerja dosen dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian dan pengadian kepada masyarakat. Prestasi kerja dosen yang dimaksudkan adalah bagaimana kompetensi dan kapasitas dosen dalam peran sertanya dalam mengikuti konferensi, seminar. Dosen sebagai pembicara atau pembicara utama pada taraf nasional dan internasional. Kompetensi lain yaitu dalam menulis artikel pada taraf internasional yang bereputasi atau yang terindeks. Prestasi lain yang dapat ditunjukkan oleh seorang dosen antara lain, sebagai reviewer pada taraf internasional. Dosen memenangkan kompetisi pada taraf nasional maupun internasional, berperan aktif dalam organisasi sebagai ketua pada taraf intenasional.
Upaya peningkatan kinerja dosen merupakan salah satu aspek dalam pelaksaanan sistem penjaminan mutu secara internal yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan tentang mutu di perguruan tinggi biasa telah dituangkan dalam standar pendidikannya. Peningkatan kinerja dosen merupakan bentuk perwujudan dalam pembenahan mutu dalam manajemen sumber daya manusia di suatu perguruan tinggi. Hal itu dilakukan sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada Stakeholders bahwa penyelenggaraan pendidikan dijamin bermutu. Kewajiban dosen telah diatur dalam Undang-undang bahwa dosen harus memiliki gelar magister untuk menjadi dosen program diploma dan Sarjana. Dosen juga dipersyaratkan memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, dan memiliki sertifikat pendidik. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikat adalah telah pengalaman kerja minimal 2 tahun dan lulus sertifikasi. Persyaratan lain adalah memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kom-petensi social. Disamping itu ada beberapa persyaratan seperti sehat jasmani, rohani, dan persyaratan lain yang tetapkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
Pengukuran kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya dalam setiap semester dengan perhitungan rencana beban kerja dosen (R-BKD) setiap awal semester. Di samping itu juga harus dilaporkan juga kinerja dosen untuk kinerja dosen pada semester yang sudah dilaksanakan (LKD). R-BKD merupakan kontrak kerja dosen yang akan dilaksanakan pada satu semester berikutnya. R-BKD dam LKD dihitung jumlah sistem kredit semester (sks) antara 12 sks sampai dengan 16 sks. Jumlah sks
108 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tersebut yang dituangkan dalam rubrik adalah nilai maksimum yang selanjutnya diassesmen oleh asesor untuk menentukan nilai akhir. Pelaporan LKD dan R-BKD harus menggunakan rubrik yang telah ditetapkan. R-BKD atau kontrak kegiatan tridarma dan hasil pelak-sanaannya tidak boleh kurang batas minimum, yaitu 12 sks. Bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja tridharma minimal 12 sks, maka akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan. Pengisian R-BKD dan LKD telah disusun program aplikasinya yang memuat langsung perhitungan sks yang diperoleh oleh dosen. Perhitungan sks pada beban kerja dosen (BKD) telah dibedakan bagi dosen yang tugas belajar dan ijin belajar S-3.
Berdasarkan hasil kajian tentang kinerja dosen dalam perspektif manajemen sumber daya manusia bahwa pengukuran kinerja dosen tersebut kurang lengkap. Permasalahan yang muncul kinerja dosen yang diukur hanya dalam aspek output dan outcome. Sedangkan pada aspek perencanaan dan proses belum diukur. Aspek perencanaan yang meliputi rencana pembelajaran semester (RPS), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, kontrak kuliah. Aspek proses yaitu pelak-sanaan perkuliahan, pelaksanaan praktikum, dan pelaksanaan evaluasi ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS). Hal itu perlu dilakukan mengingat pengukuran kinerja dosen hanya pada aspek output dan dan outcome saja tidak cukup. Pengukuran tersebut belum dapat menggambarkan aktifitas dosen yang sesungguhnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pengukuran kinerja hanya mengukur perolehan sks dalam satu semester yang sudah dilaksanakan, tetapi tidak mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaannya. Hal itu berarti tidak menggambarkan bagaimana perencanaan, proses pelak-sanaan dan evaluasi secara utuh yang sesuai dengan prinsip manajemen.
Pembahasan
Kinerja
Kinerja atau performance banyak orang mengartikan sebagai penampilan, hasil prestasi atau tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok. Kinerja dapat didefinisikan sebagai unjuk kerja, hasil kerja dan prestasi seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai apa yang dicapai, prestasi yang ditunjukkan, kemampuan kerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan apabila indikatornya sudah ditetapkan dan pengukurannya dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Organisasi atau lembaga apabila untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, target, sasaran
New Normal, Kajian Multidisiplin | 109
dapat menggunakan pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan pada saat perencaan, pelaksanaan dan pada saat berakhirnya suatu pekerjaan. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk mengetahui secara kualitatif kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas. Kompetensi tersebut antara lain adalah kompe-tensi kepribadian, social, profesional dan kompetensi dalam penguasaan bidang yang digeluti. Banyak para ahli yang mendefisikan kinerja secara berbeda-beda namun dalam defisininya lebih menekankan pada hasil kerja atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok invidu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja beberapa diantara-nya adalah kedisiplinan, dan kepuasan dalam bekerja. Kepuasan dalam bekerja adalah sesuatu yang sangat dirasakan oleh pekerja, sehingga mereka akan bersemangat untuk bekerja yang lebih baik. Kedisiplinan harus juga ditegakkan, tanpa adanya penegakan kedisiplinan mereka akan bekerja sesuai dengan tata tertib atau prosedur yang ditetapkan. Pekerja apabila disiplin dan merasa puas terhadap pekerjaannya, maka akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap lembaga atau organisasi [1]. Selain itu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kompensasi, lingkungan kerja, dan Gaya kepemimpinan, namun faktor yang sangat esensial adalah kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Lingkungan kerja seperti hubungan kerja sesama pekerja dengan pimpinan yang baik akan meningkatkan kinerja pekerja atau pegawai. Hal itu disebabkan oleh perasaan pekerja merasa akrab dengan sesamanya dan dekat dengan pimpinan. Gaya kepemimpinan seperti pemimpin memperlakukan pegawai secara adil dan memberikan rasa nyaman dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja [2].
110 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Pengukuran kinerja sangat diperlukan memperhatikan visi, misi, tujuan organisasi dalam strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Hal itu dilakukan agar manajemen sumber daya manusia mengetahui apakah tindakannya pada satu perspektif akan mendukung perspektif lainnya [3]. Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard, yaitu perspektif finansial. Perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif finansial akan melihat kinerja dalam sudut pandang hasil apa yang dike-hendaki oleh stakeholder. Perspektif pelanggan akan melihat tingkat kepuasan pelanggan. Perspektif Proses Internal akan melihat tentang proses sudah sesuai dengan harapan dan mengalami peningkatan. Pespektif pembelajaran dan pertumbuhan akan melihat hasil pengem-bangan baru walaupun bersifat jangka panjang dan sebagai pembelajaran organisasi. Adapun perspektif tersebut akan dikembang-kan indicator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah perspektif-perspektif tersebut sudah sesuai dengan harapan [4]. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu pelaksanaan pekerjaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan organisasi adalah kinerja. Visi, misi, tujuan organisasi biasanya tertuang dalam rencana strategis (renstra) suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menggambarkan prestasi atau tingkat keberhasilan. Kinerja dapat diketahui keberhasilannya jika terdapat kriteria atau indicatornya yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksudkan adalah tujuan-tujuan apa yang akan dicapai. 1.1. Pengukuran Kinerja Dosen Pengukuran kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya setiap semester dengan perhitungan beban kerja dosen yaitu R-BKD dan LKD. R-BKD adalah Rencana Beban Kerja Dosen (R-BKD) adalah perhitungan kontrak kerja dosen pada awal semester. LKD adalah Laporan Kinerja Dosen adalah perhitungan kinerja dosen semester sebelumnya. R-BKD merupakan gambaran beban kerja dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester yang akan dilaksanakan dihitung SKS nya. LKD merupakan gambaran kinerja dosen yang sudah melaksanakan tridharma dalam satu semester dihitung sks. Beban minimum sks R-BKD dan LKD adalah 12 sks dan maksimum 16 sks per-semester. R-BKD dan LKD diatur dalam rubrik antara lain, Kegiatan yang direncanakan mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang yang dilaksanakan pada setiap
New Normal, Kajian Multidisiplin | 111
semester. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang digabung paling sedikit sepadan dengan 9 sks. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan masing-masing di Perguruan Tinggi. Kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat serta bidang penunjang harus direncanakan serta ada sks yang akan dikerjakan. Bagi dosen yang memiliki tugas tambahan (DT) di Perguruan Tingginya otomatis memiliki 3 sks beban paling rendah dibidang pendidikan. Hal itu diberikan dengan disesuai-kan pada jabatan atau dengan tugas tambahannya. Tidak diperkenan-kan terdapat beban sks yang kosong. Baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian, untuk DS dan DT . Perhitungan keseluruhan R-BKD sks yang akan dilaksanakan minimal 12 sks. Penyampaian LKD telah diatur dalam Rubrik yang telah disediakan, antara lain, LKD harus diisi untuk semua kegiatan dosen setelah melaksanakan tridharma. Laporan tersebut wajib disertai bukti nyata untuk diunggah. Perhitungan keseluruhan kinerja dosen memuat jumlah beban minimal 12 sks. Kelebihan beban sks tridharma harus dilaporkan seluruhnya wajib disertai bukti nyata. LKD yang terdiri dari gabungan bidang pendidikan dan penelitian, minimal 9 sks untuk dosen DS maupun DT. Aplikasi BKD yang telah diprogram sudah tersedia kinerja langsung bidang pendidikan, minimal 3 sks bagi DT. Aplikasi tersebut juga sudah tersedia kinerja bidang pendidikan 12 sks untuk dosen yang sedang melaksanakan pendidikan untuk program doktor. Aplikasi dosen yang melaksanakan untuk pendidikan lanjut tersebut berlaku untuk Dosen Tugas Belajar (DTB) dan Izin Belajar (DIB). DTB maupun DIB wajib melaporan perkembangan studinya dengan mengunggah bukti nyata. Hal itu dilakukan Sebagai bukti dosen profesional, sedang melaksanakan studi lanjut. Fasilitas Aplikasi BKD dapat menghitung kinerja akhir yang merupakan hasil assesmen yang dilakukan oleh BKD. Bagi Dosen yang tidak memperoleh minimal kinerja minimum 12 sks, maka akan diberikan sangsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dosen yang telah memperoleh kinerja di atas 12 sks akan dihitung oleh internal Perguruan Tinggi sebagai beban kerja lebih. Tugas utama dosen di perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. beban kerja dosen minimal sepadan dengan 12 sks dan maksimal 16 sks untuk setiap semester. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut, melaksanakan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian minimal sepadan 9 sks. Beban beban pendidikan dan pengajaran mini-
112 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mal 6 sks untuk kegiatan di program S1. Dosen dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib ada, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan lembaga lain. Dosen dalam melaksanakan bidang Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai perhitungan beban sks yang telah ditetapkan. Pelak-sanaan Pengabdian dan Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi dihitung minimal 3 SKS; Pelaksanaan kewajiban khusus bagi Profesor sekurang‐
kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun. Kewajiban bagi Pemim-pin perguruan tinggi adalah memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. [5] Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian sebagaimana yang tertuang dalam tugas utama maupun tambahan adalah beban kerja dosen. Beban kerja tersebut yang harus diemban dosen maupun dosen yang telah memiliki jabatan akademik professor. Selain kegiatan tridharma sebagai tugas utama juga tugas penunjang dan tugas tambahan yang dilaksanakan olek dosen akan dinilai sksnya. Penilaian tugas-tugas dosen yang dilakukan dosen secara proporsional tersebut ketentuan yang telah ditetapkan. Besaran sks yang diperoleh menggambarkan beban tugas dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Pedoman beban sks yang telah telah ditentukan dalam rubrik perhitungan sks merupakan beban minimal bagi dosen. Dosen diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan tridharma dan penunjang dalam membangun bidang keilmuannya untuk meningkatkan keprofesionalan dosen. Penilaian beban kerja dosen merupakan gambaran rekam jejaknya terhadapat keprofesionalan seorang dosen, yang dinilai secara On-line untuk setiap semesternya. Laporan kinerja dosen yang dilaporan setiap semester dilaporkan ke Dirjen Dikti setelah diverifikasi oleh asesor [6]
Beban Kerja Dosen
Beberapa pakar mendifinisikan Beban kerja yang sesuai dengan perspektif bidang yang dikerjakan. Sampai saat ini definisi beban kerja belum ada memiliki definisi yang dapat diterima secara luas. Menurut beberapa ahli pengertian definisi sebenarnya tidak dapat dikatakan salah atau benar, definisi dinyatakan salah atau benar tergantung penerapannya. Definisi beban kerja di lingkungan pemerintahan, beban kerja didefinisikan sebagai hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan aturan waktu waktu. Volume atau ukuran pekerjaan yang harus diemban oleh suatu pejabat atau lembaga. Berdasarkan peraturan per-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 113
undang-undangan Beban kerja dosen adalah mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran adalah dalam bentuk penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pem-belajaran, melaksanakan proses dan evaluasi pembelajaran. Di samping itu juga melakukan pembimbingan, melatih mahasiswa, melakukan tugas tambahan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja dosen dapat didefinisikan sebagai banyaknya tugas yang dipikul, diemban dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang. Setiap pekerja merupakan beban bagi dosen, berupa beban fisik maupun beban mental. Memperhatikan perspektif ergonomi, beban pekerjaan adalah tugas yang diterima oleh seseorang dosen yang diseimbangkan dengan kemampuan fisik, kognitif dengan keterbatasan dosen dalam menerima beban tersebut. [7]. Beban kerja dosen adalah suatu hubungan antara volume kemampuan sumber daya dan volume yang dibutuhkan dosen dalam melaksanakan tugas. Beban kerja dosen merupakan interaksi antara tuntutan tugas tridharma di perguruan tinggi dengan kompetensi dan persepsi dari dari dosen. Beban kerja dosen dapat pula didefinisikan sebagai tuntutan tugas, yaitu tridharma. Beberapa pendapat yang berbeda dengan mendefinisikan beban kerja muncul disebabkan terdapat perbedaan antara kemapuan dosen dengan tugas melaksanakan tridharma. Beban kerja juga dirasakan dapat muncul akibat tuntutan harus dikerjakan dengan waktu yang tersedia tidak cukup. Beban kerja timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas yang dimiliki seseorang. Keterbatasan tersebut berakibat timbulnya kegagalan dalam kinerja. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beban kerja dosen adalah banyaknya tugas-tugas yang harus emban dosen. Tugas-tugas yang mencakup kegiatan pokok yaitu pelaksanaan tridharma dan penunjang, dengan penilaian sebagaimana yang tertuang dalam rubrik BKD.
Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang bersedia dan mempunyai kompetensi untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi. SDM dalam pembahasan ini adalah dosen, sedang organisasi adalah perguruan tinggi. Sehingga Sumber daya manusia yang dimaksud adalah dosen yang bekerja di suatu perguruan tinggi. SDM sebagai faktor yang esensial, selain tenaga kependidikan, mahasiswa dalam menentukan kualitas dan kemajuan suatu perguruan perguruan tinggi. Hal itu dapat dilihat dari budaya dan karakteristik perguruan tinggi
114 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dalam pembentukan kualitas civitasnya. Beberapa faktor dari SDM adalah kompetensi, Sikap, nilai-nilai, kebutuhan dan karakteristik demografisnya. Kompetensi terdiri dari, keahlian, potensinya. Di samping itu juga intelegensi, ketrampilan khusus maupun umum serta bakat yang dimilikinya. Faktor lingkungan seperti budaya, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi faktor-faktor SDM tersebut. Peranan dan perilaku manajemen akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas. Sehingga hal itu menjadikan dasar bahwa peranan dan perilaku pimpinan perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimiliki oleh dosen. Manajemen SDM di perguruan tinggi memiliki fungsi antara lain fungsi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan dan penilaian SDM. Ada juga yang berpendapat bahwa fungsi manajemen SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, leading atau penggerakan, dan controlling atau pengendalian. . Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah proses pemberdayaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Proses pemberdayaan tersebut melalui kegiatan perencanaan, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan oleh instansi atau lembaga. Kegiatan yang dilakukan antara lain, rekruitmen pegawai atau karyawan, selanjut diseleksi, kemudian dilakukan pengembangan karir. Dalam pelaksa-naannya juga dilakukan pemberian kompensasi, dan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kerja. Selain itu yang lebih penting lagi adalah kegiatan penilaian kinerja SDM [8]. Manajemen pengembangan SDM di perguruan tinggi merupakan proses pengelolaan tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan atau karyawan. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian dosen dan karyawan untuk mewujudkan kualitas perguruan tinggi. Hal itu diperlukan adanya internalisasi budaya perguruan tinggi untuk setiap civitas akademika. Mengkaitkan antara karakteristik individu dan kelompok dosen, karyawan yang ada di perguruan tinggi tersebut untuk saling berinteraksi dan beradaptasi. Sehingga terbentuk-nya nilai-nilai dan perilaku civitas akademika yang berbasis nilai-nilai, norma atau aturan, tradisi perguruan tinggi yang bersangkutan [9]
Fungsi MSDM
Fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengembangan, peme-liharaan dan pengendalian. Fungsi Perencanaan SDM adalah menetap-kan kriteria SDM yang diinginkan. Jangka waktu dalam perencanaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Perencanaan jumlah SDM yang dibutuhkan organisasi perlu disesuaikan dengan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 115
jumlah kebutuhan personil serta kompetensinya. Perencanaan SDM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta pengembangan dan peningkatan serta keberlanjutan organisasi. Di samping itu perencanaan SDM dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Perencanaan tersebut dapat dituangkan rencana strategis untuk pengembangan organisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu maka perencanaan SDM mereupakan suatu proses untuk menentukan suatu strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja. Strategi yang telah ditetapkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini maupun pengembangan di masa yang akan datang.
Fungsi pengembangan SDM adalah proses pengembangan sikap perilaku, pengetahuan dan ketrampilan umum maupun ketrampilan khusus tenaga kerja. Proses pengembangan juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh organisasi. Proses pengembangan hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing unit organisasi maupun secara umum untuk organisasi. Fungsi Pemeliharaan SDM adalah proses kegiatan untuk meningkatkan kondisi psikologis, kondisi fisik, loyalitas, dedikasi tenaga kerja atau karyawan. Adapun tujuan dari pemeliharaan SDM adalah untuk memberikan bekal kepada tenaga kerja agar kinerjanya lebih baik lagi sesuai dengan harapan organisasi. Mereka bekerja dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepedulian terhadap organisasi. Pemeliharaan juga menyangkut kesejahteran, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Faktor kedisiplinan tenaga kerja juga merupakan fungsi pemeliharaan SDM, karena kedisiplinan merupakan faktor utama untuk mentukan keberhasilan organisasi. Tanpa kedisiplinan tenaga kerja dalam melak-sanakan tugas-tugasnya maka tidak bisa menjamin keberhasilannya. Fungsi pengendalian SDM adalah proses kegiatan untuk mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja. Tujuan pengen-dalian SDM adalah untuk melihat dan menilai kinerja para tenaga kerja yang disesuaikan job diskription, prosedur kerja organisasi. Jika terjadi penyimpangan, maka perlu dilakukan pengarahan atau pembinaan, tetapi jika sulit untuk diarahkan maka harus diberi sanksi. Fungsi pengendalian juga dapat dituangkan kedalam peraturan atau tata tertib kerja yang meliputi kehadiran, kedisiplinan [10].
Psikologi MSDM
Psikologi MSDM adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang perilaku tenaga kerja dalam melaksanakan fungsi manajemen
116 | New Normal, Kajian Multidisiplin
untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM sendiri merupakan ilmu yag mempelajari tentang bagaimana mengartur tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari pengaturan tenaga kerja tersebut adalah agar tenaga kerja bertanggung jawab secara secara social, etis terhadap pekerjaannya. Tujuan yang lain adalah agar tenaga kerja berkewajiban meningkat efektifitas organisasi dengan upaya untuk meningkatkan produksi. Manfaat psikologi manajemen MSDM adalah sebagai berikut: (1) untuk alat mengembangan kemampuan memimpin, (2) untuk peningkatan komunikasi, (3) untuk Peningkatan kepribadian, (4) untuk pemberian motivasi, (5) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, (6) sebagai alat pengawasan kinerja, (7) sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja, (8) sebagai alat untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan, (9) untuk dalam melaksanakan mediasi, (10) untuk mengembangkan ketrampilan tenaga kerja, (11) sebagai alat menentukan mutu Kinerja, (12) untuk meningkatkan efektivitas atau produktivitas, (13) untuk menelaah Organisasi. Memperhatikan yang telah dikemukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi SDM merupakan studi yang membahas tentang karakteristik, perilaku tenaga kerja. Di samping itu psikologi SDM juga mempelajari tentang kejiwaan tenaga kerja. Sehingga dengan mengetahui karakteristik, perilaku, dan kejiwaan tenaga kerja, maka dalam manajemen dapat melaksanakan fungsinya dengan memperhati-kan hal tersebut. Salah satu contoh bagaimana memotivasi tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerjanya. Tenaga kerja yang memiliki motivasi kerja yang kuat pada dirinya, maka akan dapat membang-kitkan semangat kerjanya. Hal itu menjadikan dasar untuk melakukan pendekatan kepada tenaga kerja dalam memotivasi tentu perlu menggunakan ilmu tentang psikologi MSDM. Psikologi MSDM dapat dijadikan alat pengembangan kepemimpinan dalam organisasi, agar pemimpinnya dalam memimpin organisasi harus memahami tentang psikologi SDM. Dengan memahami Psikologi SDM, maka pemimpin mengetahui untuk memilih tenaga kerja yang tepat untuk diberikan pekerjaan yang sesuai. Pemimpin juga dapat melakukan komunikasi yang baik terhadap tenaga kerja, sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan tenaga kerja.
Psikologi MSDM sangat erat kaitannya dengan psikologi sumber daya manusia, karena dalam melaksanakan fungsinya sangat terkait psikologi. MSDM dalam melaksanakan fungsinya antara lain, mengenai penempatan, rotasi tenaga kerja maka dibutuhkan pengetahuan tentang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 117
perilaku atau kejiwaan tenaga kerja. Hal itu menunjukkan bahwa psikologi SDM merupakan faktor yang sangat esensial dalam pelak-sanaan MSDM. Pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dalam fungsi MSDM dengan memperhatikan psikologi SDM maka akan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kerja. Pendapat lain, tentang Fungsi MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Pendapat lain yang lebih lengkap menyatakan bahwa fungsi MSDM adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa MSDM dan pengem-bangan SDM yang baik atau mempunyai nilai yang tinggi, maka akan menghasilkan kinerja individu dan organisasi yang tinggi pula. Lingkungan, sosial, politik sangat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan organisasi dalam pengembangan karyawan di bidang inovasi, adaptasi atau fleksibilitas dan kemampuan karyawan. [11].
Perencanaan adalah menentukan tenaga kerja yang disesuaikan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian adalah kegiatan mengatur pembagian kerja tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan bagaimama untuk melaksanakannya. Pengarahan adalah kegiatan untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada para tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien. Pengendalian adalah kegiatan mengontrol, mengawasi tenaga kerja dalam melaksanakan tugas. Pengadaan adalah kegiatan penerimaan, seleksi, penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Pengembangan adalah kegiatan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Kompensasi adalah kegiatan pemberian imbalan atas jasa tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengintegrasian adalah proses mempersatukan kepentingan bersama antara tenaga kerja dan organisasi agar serasi selaras dan seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak. Pemeliharaan adalah proses untuk merawat kondisi psikologis, fisik, agar dedikasi dan loyalitas karyawan meningkat dalam bekerja sampai purna tugas. Kedisiplinan adalah proses memberikan kesadaran para tenaga kerja untuk mentaati peraturan organisasi. Pemberentian adalah pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh beberapa hal, misalkan kontrak kerja habis dan sebab lainya [12].
Kinerja Dosen dalam Perspektif MSDM di Masa Pandemi Covid-19
Pengukuran kinerja dosen dalam melaksanakan tugasnya setiap semester dengan perhitungan beban kerja dosen yaitu R-BKD dan LKD
118 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Adapun unsur penilaian Kinerja Dosen pada unsur Pelaksanaan pendidikan meliputi, (1) per-kuliahan atau tutorial dan memberikan bimbingan, menguji dan melaksanakan praktikum di laboratorium, di bengkel atau studio, kebun percobaan, teknologi pembelajaran dan praktek di lapangan. (2) Mem-berikan bimbingan seminar. (3) Memberikan bimbingan kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja di lapangan (4) Memberikan bimbingan dan membantu membimbing penulisan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. (5) sebagai penguji pada ujian akhir. (6) Memberikan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. (7) Menyusun pengembangan program kuliah. (8) Menyusun pengembangan bahan kuliah. (9) Melaksanakan orasi ilmiah. (10) Menjabat pimpinan perguruan tinggi.
Penilaian kinerja pada unsur Pelaksanaan penelitian meliputi, (1) menyusun karya ilmiah. (2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah. (3) Mengedit atau menyunting karya ilmiah. (4) Merencanakan karya teknologi yang dipatenkan. (5) Merancang karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental, atau seni pertunjukan, atau karya sastra. Penilaian kinerja pada unsur pengabdian kepada masyarakat meliputi, (1) Menjabat pimpinan. (2) Mengembangkan hasil pendidikan maupun penelitian. (3) Melatih atau penyuluhan atau penataran atau ceramah pada masyarakat. (4) Pelayanan kepada masyarakat dan atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. (5) Menulis karya pengabdian. Penilaian kinerja pada unsur penunjang meliputi, (1) Sebagai anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. (2) sebagai anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. (3) sebagai anggota organisasi profesi dosen. (4) Mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. (5) sebagai anggota delegasi nasional ke per-temuan internasional. (6) Berperan serta aktif dalam, pertemuan ilmiah. (7) Memperoleh penghargaan atau tanda jasa. (8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. (9) Berprestasi di bidang olahraga atau humaniora. (10) sebagai anggota dalam organisasi profesi dosen. (11) Sebagai anggota dalam tim penilai. [13].
Memperhatikan ursur-unsur penilaian kinerja dosen yang dituangkan dalam R-BKD dan LKD menunjukkan bahwa berdasarkan pespektif MSDM penilain tersebut belum sepenuhnya mengukur kinerja yang sesungguhnya. Hasil kajian tentang pengukuran kinerja dosen
New Normal, Kajian Multidisiplin | 119
berdasarkan beban kerjanya yang diukur hanya R-BKD pada aspek perencanaan berupa kontrak kerja dosen pada awal semester yang akan dilaksanakan. Perencanaan tersebut hanya berisikan rencana mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang. Perencanaan mengajar hanya ditunjukkan surat tugas mengajar, penelitian dan pengabdian hanya ditunjukkan dengan rencana proposal. Sedangkan untuk kelengkapan perencanaan yang lain misalkan rencana pembelajaran semester (RPS), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, kontrak kuliah, rencana praktikum, modul atau buku ajar tidak dilaporkan. Pada unsur pelaksanaan pembelajaran misalkan pelaksa-naan perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan dan pelaksanaan evaluasi ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) hanya ditunjukkan atau dilaporkan hasilnya saja yang berupa nilai akhir hasil perkuliahan. Sedang untuk proses perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan dan proses ujian tidak dinilai atau diassesment oleh assessor. Begitu pula untuk penelitian, pengabdian dan pelaksanaan penunjang hanya dilihat output atau outcomenya saja. Sedangkan standar proses penelitian dan pengabdian tidak dinilai atau diassesment oleh assessor.
Hal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur penilaian kinerja dosen yang dituangkan dalam R-BKD dan LKD belum sepenuhnya mengukur kinerja berdasarkan pespektif MSDM. Oleh karena itu perlu dipikirkan instrument yang dapat mengukur kinerja dosen dengan berdasarkan perspektif MSDM, dengan memperhatikan aspek peren-canaan yang sesuai perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran. Di samping itu juga memperhatikan aspek perencanaan dan proses penelitian maupu pengabdian dengan mendasarkan pada standar prosesnya. Mengingat Fungsi pengembangan MSDM adalah proses pengembangan sikap perilaku serta fungsi pemeliharan adalah proses kegiatan untuk meningkatkan kondisi psikologis, kondisi fisik, loyalitas, dedikasi tenaga kerja atau karyawan, maka dalam mengukur kinerja dosen juga harus memperhatikan perilaku dan kondisi psikologisnya.
Kondisi psikologis dosen saat melaksanakan tridharma pada masa pandemi Covid-19 banyak yang mengalami stress, burnout dan low Self-esteem. Hal itu terjadi ketika saat melaksanakan perkuliahan yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi pada masa pandemi covid-19 ini perkuliahan dilaksanakan secara Daring atau online. Hasil pengamatan menunjukkan bahawa para dosen mengalami kesulitan untuk melaksanakan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat secara daring. Waupun sebagian dosen mampu melaksana-
120 | New Normal, Kajian Multidisiplin
kan penelitian dan pengabdian secara daring, tetapi itupun terbatas. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penilaian kinerja dosen pada saat masa pandemi covid-19 ini. Sebagian dosen mengalami stress, burnout yang disebabkan secara psikologis kondisi saat pandemi tersebut merasa resah, ketakutan, kurang percaya diri, merasa terbebani dengan pekerjaan yang tidak seperti biasanya ketika belum terjadi pandemi ini.
Perkuliahan yang dilaksanakan kurang efektif, hal itu dapat ditunjukkan pada satu semester yang telah berjalan dengan beberapa dosen yang masih mengalami kesulitan untuk melaksanakan kuliah daring. Dosen dan mahasiswa belum terbiasa melaksanakan kuliah dengan menggunakan Zoom, e-learning, dan sistem lain. Dosen dan mahasiswa merasa terbebani dengan menggunakan sisten tersebut. Di samping itu mahasiswa juga merasa terbebani paket pulsa untuk internat, walaupun sebagaian perguruan tinggi sudah memberikan subsidi untuk pulsa internet. Banyak para mahasiswa yang kurang bersemangat untuk kuliah online ini, begitu pula dosen yang kurang menguasai e-learning juga kurang punya semangat untuk melaksana-kan perkuliahan online ini. Di sisi lain, bagi dosen yang memiliki semangat untuk belajar menguasai model pembelajaran e-learning ini, maka mereka berusaha dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran online tersebut. Begitu pula pelaksanaan praktikum, kuliah lapangan, kuliah kerja nyata juga kurang efektik, yang disebabkan oleh adanya aturan protokoler dan pemberlakukan PSBB atau Social distancing. Setiap Orang Diharapkan untuk menjaga jarak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dilarang untuk melakukan kerumunan atau mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, himbauan untuk tinggal di rumah.
Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait dengan pengukuran kinerja dosen dengan pedoman dan rubrik berlaku saat ini, yang menunjukkan adanya kekurangan dari aspek penilaian, maka sangat diperlukan pemikiran untuk penyempurna-annya. Salah satu penyempurnaannya adalah unsur-unsur yang belum dinilai dalam R-BKD dan LKD tersebut walaupun tidak diunggah tetapi tetap dinilai secara internal oleh assesor internal yang berasal dari perguruan tinggi dosen yang dinilai. Di samping itu juga dalam penilaian kinerja dosen perlu memperhatikan kondisi psikologis dari dosen, apalagi pada masa pandemi covid-19 saat ini. Mengingat saat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 121
masa pandemi ini banyak para dosen yang mengalami beban psikologis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
Rujukan
[1]. Ririn N. I. S. and Hady. S, H., “Peningkatan Kinerja pegawai Melalui Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja (Reach employee performance by job performance and work discipline), “ J. Pendidikan Manajemen Perkantoran., Vol.1, No.1, pp. 204-214, 2016. http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper/article/view/00000.
[2]. Fatimah et al., “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017),” e-j. Riset Manajemen Program Studi Manajemen. Vol. 8 No. 15, 2019. www.fe.unisma.ac.id
[3]. Raditya A. et al., “Pengukuran Kinerja Sumber Daya manusia Dengan pendekatan Human Resources Scorecard,” J. Ilmiah Teknik Industri, Vol. 6, No. 3, pp. 185-194, 2018. www.researchgate.net/publication/33413541.
[4]. Ramadhani and Erlin T. “Perancangan Balanced Scorecard sebagai Pengukuran Kinerja pada PT Asuransi MSIG Indonesia,” J. Manajemen dan Organisasi, Vol. VII, No. 2, 2016, DOI: 10.29244/jmo.v7i2.16677.
[5]. Universitas Andalas, “Pedoman Penilaian dan Evaluasi Beban Kerja Dosen untuk Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,” Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), 2018. Padang.
[6]. Universitas Jember,”Pedoman Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen,” 2018.
[7]. Tarwaka, “Ergonomi Industri Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi di Tempat Kerja,” Surakarta: Harapan Press. 2015.
[8]. Sedarmayanti,” Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT Refika Aditama.2017.
[9]. Rochdi W. at al., “Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berbasis Budaya Organisasi melalui Implementasi Teori Z,” majalah ekonomi dan bisnis, value added, Vol. 11. No. 2, ISSN 1693-3435. 2015.
122 | New Normal, Kajian Multidisiplin
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/1773/1817
[10]. Fabiani S. and Sisca E. F.,” Identifikasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Usaha Menengah (Studi Pada CV. Kota Agung),” J. Wacana ekonomi, Fakultas ekonomi universitas Garut, Vol. 18, No. 1, pp. 001-012, ISSN 14512-5897, 2018. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/454/436
[11]. Nicole R., “Human resource management and human resource development: Evolution and contributions. ”CreightonJ. of Interdisciplinary Leadership, Vol. 1, No. 2, , pp. 120 – 129. 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.17062:CJIL.v1i2.19
[12]. Malayu S.P.H., “Manajemen Sumber Daya Manusia,” Edisi Revisi Jakarta : Bumi Aksara. 2016.
[13]. Ida Bagus G. U., “Prosedur Dan Unsur Penilaian Beban Kerja Dosen (Bkd) Dan Laporan Kinerja Dosen (Lkd),” Disampaikan Pada Sosialisasi Dan Pelatihan Bkd-Lkd Di Lingkungan Lldikti Wilayah Viii Bali Denpasar. 2019. https://docplayer.info/122400101-Prosedur-dan-unsur-penilaian-beban-kerja-dosen-bkd-dan-laporan-kinerja-dosen-lkd.html.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 123
Bab 9
Eksplorasi Geografi Emosi Guru dalam Mengelolah Kelas Daring Selama Pandemi Covid-19 Khoiriyah9 dan Fathur Rohman10
Pengantar
Selama delapan bulan terakhir di tahun 2020 ini, pandemik covid -19, wabah yang berasal dari Wuhan China, merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Setelah penyebarannya di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia mulai bulan Januari hingga bulan Agustus 2020 berdampak pada seluruh aspek kehidupan sehingga masing-masing negara mengeluarkan kebijakan masing-masing di negaranya. Di Indonesia, wabah pandemic Covid-19 dinyatakan sebagai wabah yang mengharuskan penduduknya melakukan lock down pada akhir bulan Maret 2020. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan lock down atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Segala aktifitas di luar dan di kantor semuanya dikendalikan dari rumah yang lazim disebut dengan work from home (WFH). Hal ini terjadi dalam dunia pendidikan dan pengajaran dimana biasanya guru dan murid melakukan interaksi langsung. Suasana pembelajaran lebih leluasa memberi peluang guru dan murid untuk face-to-face [1] dalam menyam-paikan materi dan guru lebih leluasa merancang pembelajaran serta mengelolah kelas. Namun pengelolaan kelas selama masa pandemic Covid-19, baik guru maupun siswa harus berinteraksi dengan jarak jauh karena harus menerapkan social distancing.
Selama masa social distancing, pembelajaran yang dilakukan jarak jauh mengakibatkan banyak hal yang harus diperhatikan oleh guru dan murid antara lain; pertama, bagaimana pola interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kedua, bagaimana pola mengatur formasi tempat duduk [2]. Ketiga, bagaimana pola penyampaian materi dan pemberian tugas. Keempat, bagaimana bentuk tugas yang diberikan. Kelima, bagaimana pemanfaatan teknologi yang digunakan. Keenam, bagaimana akses internet yang digunakan. Ketujuh, bagaimana
9 Khoiriyah, M Pd. Dosen Program Studi Tadris Bahasa Inggris, IAIN Jember 10 Fathur Rohman, M Pd. Guru Biologi SMP Negeri 9 Pasuruan
124 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dukungan sekolah, pemerintah serta kesiapan orang tua dalam menghadapi model pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 ini. Dengan berbagai macam persiapan yang harus dilakukan oleh guru dalam mengelolah kelas, maka diperlukan kesiapan dalam berbagai hal terkait dengan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi tertentu atau pem-belajaran secara daring.
Model pembelajaran selama pandemic Covid-19 yang mengharuskan guru dan siswa tidak bisa bertatap muka, membutuhkan pengelolaan waktu yang cukup menguras tenaga dan pikiran serta finansial untuk menyediakan koneksi internet [3]. Bagi seorang ibu maupun ayah sekaligus pemimpin keluarga yang berprofesi sebagai guru membutuhkan pengelolaan waktu yang luar biasa dalam mengelolah kelas daring selama pamdemi. Hal ini yang menarik perhatian peneliti bagaimana seorang ibu yang harus mendampingi putra putrinya belajar secara daring di rumah, sementara dia juga harus mengajar siswa di sekolah secara daring juga. Begitu pula dengan ayah, mereka harus menyiapkan gawai untuk putra-putrinya sementara dia juga harus memiliki gawai dan koneksi internet yang cukup lancar untuk melaksanakan kelas daring. Kondisi seperti ini memerlukan alokasi dana yang cukup untuk menyediakan alat teknologi atau gawai yang mendukung.
Walaupun banyak penelitian yang membahas masalah pengelolaan kelas namun jarang yang memperhatikan emosi geografi yang dialami seorang ibu maupun ayah yang merangkap sebagai guru pada masa pandemic Covid-19. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi geografi emosi guru yang merangkap sebagai orang tua dalam mengelolah kelas secara daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan (1) bagaimana pola interaksi guru dan murid selama pembelajaran daring pada saat pandemic Covid-19?, (2) bagaimana perbedaan mengelolah kelas antara ibu yang merangkap sebagai seorang guru dan ayah yang merangkap sebagai seorang guru pada masa pandemic Covid-19? (3) bagaimana kebijakan pembelajaran daring mempengaruhi aktifitas bagi seorang guru yang harus mendampingi putra-putrinya di rumah dengan menggunakan pembelajaran daring?.
Pada penelitian ini, narrative inquiry [9] digunakan untuk menggali data tentang geografi emosi guru dalam mengelolah kelas secara daring dengan merujuk pada Hargreaves [4] tentang geografi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 125
emosi sebagi alat konseptual analitis dengan lima kategori geografi emosi yaitu: Socio-cultural geography, Moral geography, Professional geography, Physical geography, dan Political geography [5], [4], [6], [7], [8]. Adapun partisipan pada penelitian ini adalah dua orang guru yang masih memiliki putra putri yang bersekolah di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap guru guru lain yang mengalami permasalahan yang sama.
Geografi Emosi
Geografi emosi pada penelitian ini mengadopsi teori Hargreaves [5], [4], [6], [7], [8] dengan mengelompokkan lima katagori geografi emosi yaitu: Socio-cultural geography, Moral geography, Professional geography, Physical geography, dan Political geography.
Geografi sosiokultural
Geografi sosiokultural merujuk pada kedekatan dan/atau jarak yang diciptakan oleh perbedaan gender, ras, etnik, bahasa, dan budaya. Guru laki-laki dan guru perempuan dari daerah yang berbeda, dari pelosok desa dan kota, memiliki kebiasaan yang berbeda dan cara yang berbeda. Perbedaan ini akan sangat terlihat ketika mereka berinteraksi dengan siswanya dan juga dengan putra putrinya di rumah. Perbedaan gender, ras, etnik, bahasa, dan budaya akan memunculkan perbedaan emosi yang berbeda pula.
Geografi moral
Geografi moral merupakan geografi yang berkaitan dengan kedekatan dan/atau jarak yang diciptakan oleh perbedaan tujuan dan indra pencapaian dalam praktik professional. Ibu maupun bapak yang berstatus sebagai seorang guru akan dihadapkan pada masa yang amat sulit dan rumit ketika mereka tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah sehingga mereka harus membawa tugas tersebut ke rumah. Dengan kondisi demikian tugas yang semestinya dia selesaikan di sekolah, ketika dibawah kerumah, maka akan menyita waktu keluarga untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga porsi waktu untuk keluarga tersita oleh penyelesaian tugas. Hal ini akan berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga serta kesehatan mentalnya jika tidak diiringi dengan sikap spiritual yang kuat.
126 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Geografi professional
Geografi professional menjelaskan seberapa dekat atau jauh yang diciptakan oleh perbedaan pemahaman norma professional dan praktik professional. Perbedaan budaya akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap praktek profesionalisme. Ibu guru yang berada di daerah pelosok desa akan memahami praktik profesionalisme yang berbeda dengan bapak guru yang berasal dari kota.
Geografi fisik
Geografi fisik berhubungan dengan kedekatan atau jarak yang diciptakan oleh ruang dan waktu. Karena mengajar secara daring yang membutuhkan gawai yang mutahir seperti teleponan seluler Android dengan aplikasi Zoom, Google classroom, maupun Quipper class serta koneksi internet dan signal yang bagus, maka guru harus dilengkapi dengan alat teknologi tersebut. Begitu pula dengan siswa yang juga menggunakan alat yang sama untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ketika hal tersebut dialami oleh seorang guru yang sekaligus dia adalah orang tua yang memiliki putra-putri yang masih duduk di bangku SD maupun SMP dimana anak-anak tersebut masih tergantung pada gawai yang sama dengan profesi yang diperlukan oleh ibunya maka hal yang amat sulit dan rumit akan dialami oleh kedua belah pihak.
Geografi politik
Geografi politik menjelaskan kedekatan/jarak yang diciptakan oleh perbedaan pemahaman tentang kekuasaan. Dalam konteks pem-belajaran daring di masa pandemi COVID-19, bapak atau ibu yang berstatus sebagai guru juga harus mematuhi kebijakan yang berlaku mengenai sistim pembelajaran dimana mereka bertempat tinggal.
Konteks Penelitian
Bapak dan ibu yang berprofesi sebagai guru dipilih sebagai partisipan karena mereka memiliki kompleksitas aktivitas yang luar biasa. Disatu sisi mereka harus bekerja secara profesiaonal sebagai guru yang harus membimbing siswa dengan menggunakan moda daring sementara disisi lain dia juga harus mendampingi putra putrinya di di rumah dengan cara yang sama. Selain itu waktu untuk memberi pelayanan terbaik untuk istri maupun suami juga harus dia lakukan mengingat suami maupun istri juga butuh perhatian. Kedua partisipan ini berasal dari dua tempat yang berbeda, partisipan 1 adalah seorang ibu
New Normal, Kajian Multidisiplin | 127
yang berprofesi sebagai guru dan berasal dari pelosok desa sedangkan partisipan dua adalah seorang bapak yang berprofesi sebagai guru dan berasal dari kota. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau work from home (WFH) sepertinya guru tidak berbuat apa-apa karena tidak hadir ke sekolahan untuk mengajar sehingga stereotype masyarakat terhadap guru pada masa pandemi tidak melakukan aktivitas mengajar sehingga di masa pandemi ini guru sering mendapatkan predikat “makan gaji buta” dari warganet dalam dunia maya. Pasuruan dipilih sebagai latar dalam penelitian ini karena kota kecil ini adalah titik temu antara kota-kota besar dalam propinsi yaitu antara Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi, begitu pula sebaliknya. Begitu juga dari jalur selatan yaitu Malang – Pasuruan – Probolinggo – Jember - Banyuwangi sehingga Kota kecil ini sebagai titik temu penyebaran wabah COVID-19 hingga pada masa normal baru masih dalam kategori zona merah sehingga mereka tidak diperkenankan melakukan pembelajara tatap muka. Pada penelitian ini, desain penelitian naratif [9] digunakan untuk menggali informasi para partisipan untuk mengetahui cerita kehidupan serta pengalaman seseorang dalam konteks tertentu untuk dimaknai menjadi sebuah pengalaman yang bermakna [10]. Dalam penelitian naratif ini, peran peneliti harus sangat berhati-hati dalam menggali informasi dan menganalisa data informasi karena peneliti kedua yang juga sebagai kolaborator partisipan adalah perpanjangan informasi dari pemikiran partisipan. Oleh karena itu peneliti kedua yang juga sebagai kolaborator harus berkali kali melakukan konfirmasi terhadap partisipan supaya mendapatkan informasi pengalaman yang benar. Kedua peneliti yang bertempat tinggal di kota kecil Pasuruan ini akan mendukung data yang akurat dalam memberi informasi karena sudah mengenal baik letak geografi maupun demografi dari kota dimana tempat penelitian ini diambil.
Pengumpulan dan Analisa Data.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Pertama-tama partisipan dihubungi untuk dimintai kesedia-annya menjadi partisipan dalam penelitian. Setelah bersedia, protokol wawancara dikirimkan kepada partisipan melalui WhatsApp dan minta persetujuan untuk melakukan wawancara. Pada saat wawancara yang dilakukan selama tiga kali yaitu pada tanggal 22 Juni 2020, wawancara kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020, sedangkan wawancara ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020 susah dengan durasi
128 | New Normal, Kajian Multidisiplin
waktu masing-masing partisipan 50 menit setiap kali wawancara. Partisipan lebih nyaman menggunakan voice note karena mereka bebas berekspresi senang, wawancara pertama dilakukan, sedih, maupun tertekan dengan menggunakan intonasi tertentu dibandingkan dengan menulis pesan di WhatsApp. Langkah selanjutnya peneliti melakukan transkrip dari hasil wawancara melalui voice note. Transkrip hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan konsep tematik [11] dengan menganalisa pola yang sering muncul dalam data melalui proses pengkodean dalam kalimat maupun frasa yang menghasilkan sebuah tema.
Adapun proses pemberian kode ini, peneliti merujuk pada teori Hargreaves [5], [6], [7], [8] yang terdiri dari lima geografi emosi yaitu socio-cultural, moral, professional, physical, dan political geography. Melalui lima geografi emosi ini maka akan muncul lima tema yang bisa didentifikasi sesuai dengan konteks bagaimana geografi emosi seorang guru dalam mengelolah kelas daring sekaligus bagaimana mendampingi putra-putrinya yang menggunakan pola yang sama pada masa pandemi COVID-19. Kelima tema tersebut merupakan tema temuan dari penelitian yang diambil sebagai tema hasil temuan.
Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara semi terstruktur dengan dua orang guru yang merangkap sebagai ibu dan bapak dari putra putri yang masih sekolah di SD dan SMP, diketahui ada dua hal pokok yang akan kami ulas dalam pembahasan ini berkaitan dengan pengelolaan kelas daring bagi siswa siswinya di sekolah serta pengelolaan pembelajaran daring untuk mendampingi putra putrinya di rumah dalam waktu yang bersamaan. Dengan kondisi demikian, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi geografi emosi guru yang merangkap sebagai orang tua dalam mengelolah kelas siswa dan mengelolah jadwal pembelajaran daring di rumah pada masa pandemic Covid-19. Adapun dua tema ini akan diulas untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diharapkan bisa memberi kontribusi pemikiran pada guru lain selama wabah pandemic Covid-19 dan pada mase normal baru ini berlangsung. Dari hasil analisa data dari wawancara terstruktur ditemukan dua tema utama yang masing masing tema akan dijabarkan menjadi beberapa sub tema. Adapun sub tema pengelolaan kelas daring yaitu (1) bentuk interaksi guru dan siswa, (2) bentuk pemberian tugas pada siswa, (3) bentuk penilaian terhadap tugas siswa, (4) penggunaan teknologi [5].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 129
Adapun penyajian data menggunakan tematik berdasarkan lima aspek geografi emosi.
Geografi sosiokultural: Meskipun tidak bertemu kusapa mereka dengan “salam”
Dalam konteks ini, kedua partisipan mengalami hal yang sama dalam hal budaya masayarakat Indonesia yang hangat. Kehangatan tersebut diungkapkan dalam bentuk memberi salam ketika bertemu dengan mengucapkan “Assalamualaikum” dengan mencium tangan pada guru. Hal ini tidak terjadi ketika pembelajaran daring berlangsung. Salam diucapkan ketika mengirim pesan lewat WhatsApp, namun mereka tidak bisa berjabatan tangan menandakan saling berkasih sayang. Selain itu bentuk kehangatan lain yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk siswa adalah mereka lebih suka berinteraksi langsung sehingga guru bisa menanamkan karakter melalui interaksi ini [12]. Masyarakat Indonesia yang cenderung lebih mengutamakan kebersamaan dalam kehangatan akan mengalami kendala ketika mereka harus dihadapkan pada pembelajaran secara individu dengan alat gawai tertentu [13]. Jadi baik bapak maupun ibu guru memiliki emosi yang sama ketika mereka tidak bisa bertemu dengan siswanya. Begitu pula sebaliknya siswa akan merindukan kehangatan sapaan salam sekaligus panjatan doa-doa dari guru ketika berjabat tangan langsung. Dari interaksi langsung inilah guru bisa menilai aspek sikap siswa sehari-hari selain dari aspek kognitif. Partisipan 1
Saya itu kalau ketemu siswa mesti mereka lari mengejar saya untuk bersalaman sambil mencium tangan atau “salim”. Saat-saat itu yang amat saya rindukan ketika harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dari sisi juga saya bisa melakukan penilaian terhadap sikap siswa saya. Kalau penilaian kognitif saya bisa mengambil dari tugas yang dia selesaikan sesuai arahan, tepat waktu, dan isinya sesuai dengan soal yang diberikan. Namun kalau dari kita tidak bisa menilai sikap mereka yang berkaitan dengan etika, akhlak, dan karakter (Pak Amin, wawancara WhatsApp, 27 Juni 2020)
Partisipan 2 adalah seorang ibu guru yang berada di desa dimana koneksi internet sangat sulit karena kendala signal sehingga informasi tentang Covid tidak begitu berdampak pada kondisi emosionalnya. Bahkan siswapun menganggap seperti tidak ada wabah sehingga ketika seorang guru menerapkan protokol kesehatan mereka cenderung mengabaikan. Apalagi memakai masker yang begitu menyiksa bagi mereka sehingga mereka bergantian memakai masker dengan kelas sebelumnya.
130 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Partisipan 2
Pake masker pun harus maksa. Kadang demi mengumpulkan tugas k sekolah, maskernya gantian dgn kelas sebelumnya. Jadi…ya anak anak merasa tidak nyaman kalau memakai masker. Mereka seperti tidak ada Covid saja, santai ke sekolah ya seperti biasanya…..(Ibu Lara, wawancara voice note WhatsApp, 27 Juni 2020)
Geografi moral: Saya atur ulang jadwal sholat berjamaahku bersama keluarga
Kenikmatan yang sangat luar biasa pada saat pandemi COVID-19 adalah ketika jadwal sholat berjamaah bersama keluarga bisa ditata ulang karena saat ini adalah saat yang hampir jarang dilakukan. Berkumpul dengan keluarga pada saat pandemi ini adalah saat dimana keluarga bisa melakukan sholat berjamaah lima waktu karena mereka tidak terikat dengan pekerjaan masing-masing. Seluruh pekerjaan dilakukan dari rumah membuat mereka lebih bisa meningkatkan spiritualitas bersama keluarga. Walaupun beban tugas yang banyak dan semua membutuhkan alat teknologi yang sama dan koneksi internet, mereka bisa mengendalikan dari rumah sehingga rumah merupakan tempat tinggal sekaligus kantor dan tempat transaksi jual beli secara online. Partisipan 1 lebih fokus pada penataan spiritual bersama keluarga sehingga mereka merasakan kenyamanan walaupun tidak bisa kemana-mana karena semuanya bisa dikendalikan dari rumah. Partisipan 1
Jadi selama pandemic COVID-19 ini kami semuanya berkumpul dimana momen seperti ini jarang kami alami, sehingga kami bisa melatih anak dan keluarga untuk tetap istiqomah berjamaah dan itu menjadi suatu komitmen. Momen seperti ini jarang kami lakukan ketika sebelum pandemic karena kita masih tergantung dengan jadwal ditempat kerja kita masing-masing. Pada saat pandemic ini, saya bebas mengatur jadwal saya termasuk sholat berjamaah karena setelah saya rasakan beban berat yang saya alami bisa mencair ketika bisa selalu bersama-sama beribadah sehingga beban berat itu bisa kita selesaikan (Pak Amin, wawancara voive notes WhatsApp, 26 Juni 2020).
Lain halnya dengan partisipan 2 yang berstatus sebagai guru di
Madrasah swasta di pelosok desa. Dia nampaknya tidak peduli dengan adanya isu COVID-19 karena dia lebih fokus pada mendampingi anaknya yang mengalami hyperactive disorder. Bagi partisipan 2 Corona itu seolah olah tidak ada sehingga dia tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terjadwal dengan tidak terang terangan. Sebaliknya siswa-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 131
siswa partisipan 2 ini juga berpendapat yang sama. Mereka menganggap tidak pernah terjadi apa-apa walaupun berita didunia maya begitu gencar tentang penyebaran dan bahaya COVID-19. Mereka bersikap seperti itu karena tidak mengikuti berita apa yang sedang terjadi. Partisipan 2
Karena anak2 tidak begtu percaya dengan adanya covid karena sudah terbawa dari rumah dan lingkungan. Kadang2 kalau kami terlalu menjaga protokoler kesehatan, mereka bilang; “covid itu ndak ada bu….”.
Geografi professional: Walaupun beban itu berat, saya harus bersikap “solutip”
Kedua partisipan mempunyai cara yang berbeda dalam menyi-kapi serta memberikan tugas pada siswa. Partisipan 1 tetap meng-gunakan protokol kesehatan yang ketat walaupun dia merasa pembelajaran daring sangat memberatkan guru karena dia juga harus mengajari putra di rumah dengan pembelajaran daring sehingga membawa pekerjaan di rumah dengan konekuensi kuota internet harus membeli sendiri dengan berlangganan wifi. Partisipan 1 adalah pak Amin (nama samaran) seorang bapak guru yang berpenghasilan cukup untuk berlangganan wifi sehingga dia tanpa ada keluhan dalam hal finansial. Namun dia harus bekerja ekstra lebih dibanding dia mengajar secara luring karena waktu yang dia gunakan tidak terikat oleh jadwa pelajaran namun dia bisa membagi waktu 24 jam itu untuk sekolah dan rumah. Walaupun dia merasa tidak puas dengan pembelajaran daring namun dia merasa datar-datar saja menyikapi kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan pak Amin adalah seorang bapak yang sudah matang secara emosional untuk berfikir dan bertindak sehingga dia harus mencari jalan keluar permasalahan yang tidak merugikan siswa dan keluarga. Mendukung dari apa yang disampaikan oleh [14] tentang kondisi pandemi ini memberi kesempatan guru, siswa dan mahasiswa untuk melakukan refleksi dan mencari jalan keluar yang lebih baik. Berikut kutipan wawancara dari kedua partisipan. Partisipan 1
Pengelolaan kelas, diutamakan dulu koordinasi dengan semua siswa mengenai cara koordinasi, dari penyampaian materi dan tugas. Daerah kami wilayah rawan covid-19 sehingga harus daring. Perasaan kurang maksimal dalam pengelolaan kelas, karena harus daring sehingga kurang cepat bisa memahami kondisi siwa dalam pembelajaran karena tidak bertatap muka langsung, namun kita harus bersikap “solutip”. Ditambah lagi kondisi siswa kami tidak semuanya punya fasilitas Hp Android dan internet
132 | New Normal, Kajian Multidisiplin
jadi harus sama-sama sabar dan telaten. Siswa juga sabar, orang tua juga sabar, terlebih adalah guru harus supper sabbar, melayani 150 siswa saya satu persatu melalui google class (Pak Amin, wawancara voice note WhatsApp, 22 Juni 2020).
Berbeda dengan pak Amin, Ibu Lara sebagai seorang guru di Madrasah swasta di desa, merasa sangat keberatan model pembelajaran daring. Ibu lara menyatakan bahwa dia tidak melaksanakan kelas daring karena sebagian besar siswanya tidak punya HP, kalau ada yang punya Hp itu mereka pinjam ke orang tua atau saudara. Dengan kondisi yang demikian ibu lara lebih baik tidak melaksanakan kelas daring daripada anak-anak harus ke warung untuk mencari koneksi internet. Ibu Lara lebih menggunakan kelas tatap muka dengan membuat jadwal sendiri dan disetujui oleh kepala sekolah melalui wakil urusan kurikulum. Jadwal pertemuan seminggu dua kali untuk menyerahkan dan mengambil tugas ke sekolah melalui wali kelas. Partisipan 2
Kadag punya hp tapi tidak punya kuota. Buka telat lagi tapi sebentar dengan protkol kesehatan Jam juga di tentukan Iy. Tp sbentar dengan protkol kesehatan Jam juga di tentukan. Serba sulit mau di beri tugas tapi tidak pernah di terangkan sehingga tidak bisa menjelaskan. Di beri video tidak bisa di buka..ya dibantu dengan LKS dengan membuat jadwal baru.Misalnya hari ini ada tugas bahasa Inggris..ada pertemuan lagi nanti ketemu hari sabtu maka pada hari sabtu itu tugas bahasa Inggris tersebut harus dikumplkan melalui wali kelas. (Ibu Lara, wawancara Voice note WhatsApp, 22 Juni 2020)
Geografi fisik: Jika tidak bertemu terasa ada yang hilang
Pengalaman kedua partisipan sama tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan siswa. Keduanya menyatakan bahwa pembelajaran secara daring tidak bisa memberi kesempatan untuk langsung berin-teraksi sehingga keduanya menunjukkan kurang antusias dan meng-alami kesulitan dalam pembelajaran. Bentuk interaksi jarak jauh dimana guru berada di rumah dan siswa juga berada di rumah hanya menyajikan kata kata dalam bentuk pesan membuat mereka merasa ada yang kurang sebagaimana respon dari partisipan 1 dan partisipan 2 tentang interaksi dengan siswa. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Moorhouse [15] tentang pembelajaran daring selama pandemi hanya memaksa guru dan siswa untuk seolah-olah mereka berinteraksi secara langsung seperti kutipan wawancara berikut.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 133
Partisipan 1
Pengelolaan kelas, diutamakan dulu koordinasi dengan semua siswa mengenai cara koordinasi, dari penyampaian materi dan tugas. Daerah kami wilayah rawan covid-19 sehingga harus daring. Perasaan kurang maksimal dalam pengelolaan kelas, karena harus daring sehingga kurang cepat bisa memahami kondisi siswa dalam pembelajran karena tidak bertatap muka langsung.(pak Amin, wawancara Whats App, 22 Juni 2020)
Partisipan 2 Ya lebih baik luring bu….karena kalau tidak bertemu anak anak terasa ada yang kurang dan anak-anak tidak begtu percaya dgn adanya covid karena sudah terbawa dari rumah dan lingkungan. Kadang2 kalau kami terlalu menjaga protokoler kesehatan, mereka bilang covid itu ndak ada bu. Di era pandemik tidak ada pembelajaran sama sekali karena masa transisi antara pandemi dan normal karena belum ada persiapan sehingga hanya menggunakan WA..tugas tugas di foto dan dikumpulkan ke sekolahan (Ibu Lara, wawancara, voice note WhatsApp, 22 Juni 2020) .
Geografi politik: Saya menghabiskan kuota internet tiga kali lipat, sedangkan saya guru honorer di sekolah swasta
Secara geografi politik, kondisi yang dialami oleh Pak Amin selaku partisipan 1 berbeda dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Lara sebagai partisipan 2. Pak Amin yang berdomisili di kota tidak mengalami kendala jaringan internet dan signal. Pak Amin juga tercukupi dengan fasilitas gawai dan jaringan internet pribadi serta signal sehingga dia tidak mengalami kendala dalam mengelolah kelas daring. Hal ini karena Pak Amin sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya bagaimana mempersiapkan kelas daring mulai dari persiapan: (1) melakukan pendataan siswa satu kelas dalam WhatsApp group, (2) mengecek kembali bagi siswa yang tidak punya gawai dan yang mempunyai gawai, (3) melakukan koordinasi bagaimana prosedur pemberian materi dan sistim penilaian yang semua dilakukan dengan menggunakan gawai WhatsApp. Dari cara menata dan merancang pembelajaran daring ini partisipan 1 lebih siap dan lebih tertata pengelolaannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penilaian, semuanya disosialisasi-kan pada siswa dengan jelas. Partisipan 1
Selagi ada signal internet saya tanggapi wajar-wajar saja, kalau memang pemerintah menyarankan untuk melaksanakan pembelajaran daring…ya saya laksanakan…kalau nanti disarankan luring, ya luring saja itu lebih baik. Walaupun membutuhkan kuota internet ya…saya
134 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bersedia menyiapkan, karena saya juga sudah lama berlangganan wifi, tinggal memaksimalkan bagaimana mengelolah dan berkomunuiikasi dengan anak-anak saja. (Pak Amin, wawancara, voice notes WhatsApp, 27 Juni 2020). Sedangkan Ibu Lara yang sehari-hari sebagai guru honorer di
sekolah swasta merasa keberatan dengan pembelajaran kelas daring karena keterbatasan kuota internet. Jatah kuota internet yang harus dia gunakan untuk melaksanakan kelas menjadi tiga kali lipat dari biasanya sedangkan dari pihak sekolah tidak ada alokasi dana untuk memberi jatah kuota internet setiap bulannya. Hasil temuan ini tidak sejalan dengan hasil temuan Baloran mengenai dukungan pemerintah terhadap penyediaan jaringan internet [16]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baloran menunjukkan bahwa dukungan pemerintah member pelayanan yang memuaskan dalam melaksanakan pembelajaran daring selama pandemic. Apalagi kapasaitas gawai Ibu Lara tidak mendukung adanya kelas daring yang lebih canggih seperti Zoom, google classroom maupun quipper class. Walaupun hanya dengan menggunakan WhatsApps, kelancaran pembelajaran akan terhambat jika tidak didukung dengan jaringan internet yang memadai apalagi menggunakan gawai yang lebih canggih karena pelaksanaan pembelajaran daring sangat tergantung dengan koneksi internet [3]. Partisipan 2
Coba kalau kami disubsidi kuota internet, mungkin kami juga bisa melaksanakan daring,,….tapi bagaimanapn sebagian besar siswa saya tidsk didukung keduanya bsik dari sisi alat maupun paketan…kalau pembelajaran luring kami masih bisa melayani anak-anak dengan menggunakan LCD jadi kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas. Kalau laptop saya sudah punya dan LCD juga di sediakan oleh sekolah, tapi pembelajaan seperti ini ya beda…masih butuh pulsa. Kami melaksanakan protocol kesehatan karena anjuran pemerintah tapi kalu pemerintah tidak member solusi ya bagaimana. Saya kadang juga tidak enak kalau ada sindiran dari tetangga: “enak sekali guru itu…tidak bekerja tapi masih di bayar..itu kan makan gaji buta”. (Ibu Lara, wawancara, voice notes WhatsApp, 27 Juni 2020)
Penutup
Karena masih banyak yang perlu diinformasikan tentang bagaimana mengelolah kelas dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka penelitian ini sangat perlu untuk dilakaukan terutama bagaimana seorang bapak dan seorang ibu guru menyikapi kondisi di
New Normal, Kajian Multidisiplin | 135
masa pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga memberi informasi bagaimana perbedaan wilayah dimana guru mengajar, keadaan financial, status guru dalam mengajar, dan juga perbedaan gender guru dalam menyikapi masa darurat wabah pandemi ini dalam mengelolah emosi mereka. Penelitian ini juga masih banyak keterbatasan untuk bisa dieksplorasi terutama dari sisi alat analisi. Oleh karena itu direkomendasikan untuk penelitian mendatang untuk mengeksplorasi fenomena lain yang lebih menantang dengan menggunakan analisis appraisal. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa dengan penerapan distance learning atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) perlu memperhatikan fasilitas yang dimiliki oleh guru maupun siswa serta kondisi psikologis mereka. Bagi guru dan siswa yang cukup secara financial maka pembelajaran jarak jauh bisa dilaksanakan walaupun ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain aspek ketrampilan siswa untuk bersosialisasi tidak bisa di terapkan.
Rujukan
[1]. S. V. Nuland, D. Mandzuk, K. T. Petrick, & T. Cooper, Covid-19 and its affects on teacher education in Ontario: a complex adaptive system perspective. Journal of Education for Teaching. 2020. https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1803050
[2]. Khoiriyah dan F. Rohman. Manajemen kelas berbasis multiple intelligence. Sidoarjo: Nizamia Learning Centre. 2015.
[3]. T. Ma, T., A. Heywood, & C. R. MacIntyre. Travel health risk perception of Chinese international students in Australia – Implication of Covid-19. Infection, Disease & Health, 25(3).197-204. 2020. DOI: 10.1016/j.idh.2020.03.002
[4]. A. Hargreaves. The emotional geographies of teachers’ relations with colleagues. International Journal of Educational Research,35(5), 503–527. 2001a. DOI: 10.1016/S0883-0355(02)00006-X
[5]. A. Hargreaves. “Mixed emotions: Teachers’ perception of their interaction with students.” Teaching and Teacher Education, 16(8), 811-826. 2000. DOI: 10.1016/S0742-051X(00)00028-7
[6]. A. Hargreaves. Emotional geographies of teaching. Teachers College Record,103(6), 1056–1080. 2001b. DOI: 10.1111/0161-4681.00142
[7]. A. Hargreaves. Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers’ emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education,21(8), 967–983. 2005. DOI: 10.1016/j.tate.2005.06.007
136 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[8]. L. Webster, & P. Mertova. Using narrative inquiry as a research method.
New York: Routladge. 2007. [9]. J. B. Schreiber, & K. Asner-Self. Educational research: The
interrelationship of questions, sampling, design, and analysis. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2011.
[10]. H. P. Widodo. Methodological considerations in interview data transcription. International Journal of Innovation in English Language Teaching and Research,3(1), 101-109. 2014.
[11]. Y. Liu. The emotional geographies of language teaching. Teacher development. 2016. [Online] Available: https://dx.doi.org/10.1080/13664530.2016.1161660
[12]. H. Purnomo, T. Tumin, F. Mansir, & S. Suliswiyadi. Pendidikan Karakter Islami Pada Kelas Online Class Management di SMA Muhammadiyah 7 Jogjakarta Selama Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 11 (1). 2020. [Online] Available: https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3456
[13]. I. Setyorini. Pandemi COVID-19 dan Online Learning: Apakah Berpengaruh Terhadap Proses Pembelajaran Pada Kurikulum 13?. Journal of Industrial Engineering & Management Research, 1(1), 95-102. 2020. [Online] Available: https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i1.31
[14]. L. L. Velle, S. newman, C. Montgomery, & D. Hyatt. Initial teacher education in England in the COVID-19 pandemic: Challenges and opportunities. Journal of education for Teaching. 2020. [Online] Available: doi.org/10.1080/02607476.2020.1803051
[15]. B. L. Moorhouse. Adaptations to a face-to-face initial teacher education course ‘forced’ online due to the COVID-19 pandemic. Journal of Education for Teaching. 2020. [Online] Available: DOI: 10. 1080/02607476.2020.1755205
[16]. E. T. Baloran. Knowledge, attitude, anxiety, and coping strategies of students during COVID-19 pandemic. Journal of Loss and Trauma. 2020. [Online] Available: DOI:10.1080/15325024.2020.1769300
New Normal, Kajian Multidisiplin | 137
Bab 10
Pelaksanaan Kegiatan KBM online di Sekolah Vokasi IPB Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan Pada Masa Covid dan New Normal Lili Dahliani11
Pengantar
Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan–China, lalu merebak dan memporak-porandakan tidak hanya perekonomian dunia tetapi juga hampir segala aspek kehidupan manusia di bumi. Data global per 17 Agustus 2020 menunjukkan 21.8 juta orang di dunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 773 ribu orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada sekitar 142 ribu orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 6229 orang diantaranya meninggal dunia (Muhyiddin dan Tribun news, 2020). Virus corona atau covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu novel coronavirus/nCov. Virus ini mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan sejumlah influenza biasa. [1]. Dampak yang ditimbulkan COVID-19 terjadi pada seluruh bidang mulai dari kesehatan, kehidupan sosial dalam masyarakat, ekonomi (pengang-guran, banyaknya PHK), hukum, hingga politik, budaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Penyakit Covid-19 telah menggerakkan pihak berwenang (para pemimpin: presiden, menteri, ketua pemerintahan, dan lain sebagainya) untuk mengambil tindakan dan keputusan dengan menerapkan sistem dirumah saja (stay at home) yakni masyarakat Indonesia diharuskan untuk diam dan bekerja dirumah masing-masing. Kebijakan dan aturan ini juga berlaku bagi pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kampus IPB khususnya Sekolah Vokasi termasuk meniadakan kuliah tatap muka diganti menjadi KBM daring (online). Menurut [2], formulasi model perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan sistem pembelajaran jarak jauh yang menggunakan bantuan teknologi, terutama teknologi
11 Dr. Lili Dahliani, Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, Sekolah Vokasi
IPB
138 | New Normal, Kajian Multidisiplin
informasi (IT), informatika. Mahasiswa dan dosen tidak perlu melakukan tatap muka selama proses pembelajaran berlangsung, semua materi dan tugas pembelajaran dilakukan secara online Beberapa penelitian terkait dengan KBM online telah dilakukan oleh [3] dan [4]. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kuliah online belum efektif sebagai media perkuliahan, karena kuliah online belum mampu menggantikan pertemuan secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara efektivitas kuliah online dalam website www.unikom.ac.id terhadap prestasi akademik mahasiswa unikom. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh kuliah online terhadap prestasi akademik mahasiswa sebesar 10,24% dan 89,76% di pengaruhi oleh faktor lain di luar kuliah online [3].
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa sistem perkuliahan daring memiliki kontribusi positif untuk menekan disparitas kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Beberapa indikasinya di antaranya adalah 1) meminimalisir keterbatasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, karena perguruan tinggi yang ada di daerah terpencil dapat mengakses pendidikan tinggi berkualitas yang ada di kota-kota besar. 2) memutus keterbatasan fasilitas yang selama ini dianggap sebagai salah satu kendala rendahnya kualitas pendidikan tinggi. Sistem kuliah daring tidak membutuhkan fasilitas yang super canggih dan mahal, cukup menggunakan PC, notebook, tablet, ataupun smartphone, yang saat ini harganya cukup terjangkau oleh masyarakat. 3) menghi-langkan keterbatasan pemahaman terhadap materi tertentu. Sistem kuliah daring memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dari pada sistem konvensional, karena materi ditampilkan secara digital dan dalam bentuk animasi. 4) Sistem kuliah daring memberikan akses yang luas terhadap sumber daya pendidikan, khususnya yang ada di perguruan tinggi tekemuka [2]. Hasil penelitian [4] menyimpulkan bahwa E-learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu belajar mahasiswa FKIP UNINUS Bandung. Semakin intensif e-learning dimanfaatkan, maka mutu belajar mahasiswa FKIP UNINUS akan semakin meningkat.
Berdasarkan kesimpulan beberapa penelitian di atas tentang penyelenggaraan KBM online menunjukkan hasil yang beragam. Mengacu kepada kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial pada masa pandemi Covid-19, penelitian yang dilakukan oleh [2] menjadi relevan karena pada saat perkuliahan dilakukan secara daring,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 139
mahasiswa dan dosen tidak melakukan tatap muka selama proses pembelajaran berlangsung dan semua materi dan tugas pembelajaran dilakukan secara online. Berbeda dengan Universitas Terbuka (UT) yang sejak semula sudah disiapkan dan didesain untuk menerapkan sistem belajar jarak jauh menggunakan media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video, computer/internet, siaran radio, dan televisi), perkuliahan online dimasa pandemi covid harus dijalankan karena situasi dan kondisi bersifat darurat kesehatan (force majeure). Kondisi ini merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga bersifat “keterpaksaan” harus dijalani. Kondisi force majeure ini menuntut kreativitas semua pihak yang terkait dengan metode KBM dalam mendesain bahan kuliah dan metode penyampaian materi kuliah agar efektif. Kajian ini memaparkan tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan KBM secara online dapat dilakukan sesuai dengan pencapaian capaian pembelaran (learning outcome) yang diharapkan.
Permasalahan KBM Online dari Rumah
Kebijakan Work from Home (WFH) diberlakukan semenjak wabah COVID-19 melanda Indonesia, tidak terkecuali Bogor yang merupakan salah satu kota dengan status zona merah. Sekolah Vokasi IPB terutama warga program studi (prodi) Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan (TMP) dalam rangka mendukung kebijakan terkait pandemi COVID-19 melaksanakan KBM online, tanpa tatap muka. Metode KBM di sekolah vokasi termasuk prodi TMP sebelum pandemi Covid-19 dirancang, didesain dan disiapkan secara offline terutama untuk mata kuliah-mata kuliah yang melatih ketrampilan motorik baik saat penjelasan teori maupun praktikum. Metode KBM yang diterapkan lebih kepada pertimbangan bahwa tujuan sekolah vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.
Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengem-bangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Sekolah vokasi secara khusus, diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri, dunia kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta serta berwiraswasta secara mandiri. Hal ini menjadikan beban KBM pada program pendidikan vokasi disusun lebih mengutamakan
140 | New Normal, Kajian Multidisiplin
beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori. Keterampilan melakukan sesuatu diperoleh jika dilakukan secara terus menerus dan dievaluasi peningkatannya setiap waktu tertentu. Proses penilaian kompetensi ketrampilan yang bersifat motorik lebih objektif dilakukan secara offline dibanding dengan online.
Mengingat Situasi dan kondisi yang dihadapi saat pandemic Covid-19, mengharuskan prodi TMP merubah metode KBM yang semula offline menjadi online. Hal ini tentunya berdampak pada efektivitas pen-capaian LO setiap mata kuliah yang diajarkan, selanjutnya berdampak juga kepada pencapaian LO program studi. LO program studi TMP adalah menghasilkan ahli madya perkebunan dan berkompetensi sebagai asisten kebun yang menguasai pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melaksanakan pengelolaan usaha produksi tenaman perkebunan. Guna mengetahui dampak tersebut, maka dilakukan jajak pendapat terhadap mahasiswa prodi TMP yang umumnya berdomisili di wilayah perkebunan, desa-desa tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kali-mantan. Jajak pendapat dilakukan dua kali, hasilnya dijelaskan sebagai berikut.
Mahasiswa TMP dan TIB serta sebagian dosen menggunakan telepon selular (Ponsel) saat pelaksanaan KBM online tersebut. Menurut [5], telepon selular merupakan media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia sehingga sistem pemancaran dan penerimaan sinyal yang sangat baik diperlukan oleh sebuah ponsel. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi penerimaan level sinyal ponsel, yaitu faktor operator/penyedia jasa layanan selular kehilangan kekuatan sinyal, faktor lingkungan yang tidak mendukung proses penerimaan sinyal atau kerusakan yang terjadi pada ponsel itu sendiri dan ini yang lebih sering terjadi. Pelaksanaan KBM online menemui kendala berupa sinyal tidak stabil dan bahkan tidak ada sinyal pada saat-saat tertentu terutama bagi mahasiswa atau dosen yang domisilinya di wilayah pedesaan, sekitar perkebunan, jauh dari kota sehingga capaian pembelajaran (learning outcome) baik kuliah maupun praktikum meng-hadapi hambatan/kendala.
Informasi dari mahasiswa bahwa yang bersangkutan harus pergi ke lokasi lebih tinggi, pegunungan agar memperoleh sinyal yang baik sehingga dapat melaksanakan KBM terutama mengerjakan tugas kuliah dan praktikum yang diberikan dosen dengan baik sesuai jadwal yang sudah disepakati. Pergi ke luar rumah bukan suatu pilihan tetapi harus dilakukan agar memperoleh lokasi dengan kondisi lingkungan yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 141
mendukung proses penerimaan sinyal. Pergi ke luar rumah melanggar himbauan “stay at home” juga suatu pelanggaran terhadap aturan lock down. Hal itu terpaksa dilakukan demi untuk mendapatkan sinyal yang baik dan stabil.
Hasil survey yang dilakukan terhadap 170 orang responden, yaitu mahasiswa Sekolah Vokasi terutama Program studi TIB (Teknis Industri Benih) dan Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan (TMP) yang berdomisili di Sumatera Utara (Padang Lawas, Labuhan Batu, Serdang Bedagi, dan kabupaten Simalungun), Riau (kabupaten Kampar), Sumatera Barat (Batu sangkar, Padang, Kampung Baru), Jawa Barat (Karawang, Indramayu, kuningan, dan Tasikmalaya), Jawa Tengah (Rembang), Jawa Timur (Blitar dan Nganjuk), dan Kalimantan Tengah (Kartamulya). Para responden tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaan KBM online karena sinyal ponsel yang labil dan kadang hilang, tidak ada sinyal di wilayah-wilayah tersebut. Mahasiswa yang berdomisili di wilayah Sumatera Barat juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan KBM online. Mengacu kepada hasil penelitian [5] bahwa kondisi lingkungan yang tidak mendukung proses penerimaan sinyal menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan KBM online. Lingkungan yang berbeda penerimaan sinyal pun berbeda. Sinyal di wilayah sumatera barat kadang blank spot area karena selain tidak adanya tower penguat juga diperberat dengann pasokan listrik dan infrastruktur.
Permasalahan sinyal yang sering terjadi pada ponsel seperti sinyal hilang, tampilan sinyal berubah (sinyal drop), sinyal tidak stabil dan sinyal penuh namun tidak dapat melakukan panggilan (sinyal semu). Untuk mengetahui masalah sinyal yang terjadi pada perangkat keras (hardware) ponsel, perlu dilakukan pemeriksaan pada rangkaian Tx dan rangkaian Rx, rangkaian CPU yang berhubungan dengan proses pengolahan sinyal serta distribusi tegangan dari IC Power Supply ke rangkaian-rangkaian tersebut. Proses pemeriksaan meliputi pemeriksaan jalur antar komponen, pengukuran tegangan dan frekuensi pada komponen yang berhubungan dengan proses pemancaran dan peneri-maan sinyal. Dengan menganalisis indikasi/ciri-ciri masalah dan hasil pemeriksaan masalah sinyal dengan teori dan fungsi tiap komponen ponsel yang berhubungan dengan pengolahan sinyal, maka dapat disimpulkan penyebab masalah dan dapat dilakukan penanganan yang sesuai dengan masalah yang terjadi. [5]
142 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Fakta di lapangan bahwa kondisi sinyal, ada atau tidak ada di
wilayah-wilayah Padang Lawas, Labuhan Batu, Serdang Bedagi berkaitan dengan pemadaman lampu oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Responden mengatakan bahwa jika di wilayah tersebut mati lampu, maka HP mereka dalam kondisi tidak ada sinyal. Pengamat tele-komunikasi mengatakan bahwa kondisi sinyal ditentukan oleh kondisi Base Tranceiver Station (BTS) milik operator seluler. Sumber tenaga BTS adalah listrik dari PLN. BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagai pemancar dan penerima jaringan seluler pada satu cakupan wilayah. BTS mengkonversi sinyal-sinyal yang dipancar-kan dan diterima menjadi sinyal digital. Sinyal-sinyal tersebut selan-jutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Listrik PLN diperlukan untuk menyalakan seluruh sistem BTS.
Hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa pelaksanaan KBM online secara umum kurang efektif dalam pencapaian LO terutama untuk kegiatan praktikum. Mahasiswa lebih mendapatkan LO dengan KBM offline dan bagi mahasiswa terjadi ineffisensi saat melaksanakan KBM online. Salah satu bentuk ketidakefektivan dari KBM online adalah maha-siswa merasa kebingungan dalam memahami materi kuliah terutama praktikum di prodi TMP, walaupun dosen memberi kesempatan untuk bertanya dan sesi diskusi. Mengingat kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberlakukan pelaksanaan KBM online di masa new normal sampai dengan tahun 2021, maka perlu dikaji ulang metode KBM online yang selama ini diterapkan di prodi TMP sehingga dapat meminimalkan hambatan yang dihadapi (jika tidak mungkin meniadakan hambatan tersebut) serta tercapai LO perkuliahan dan mahasiswa tidak terbebani biaya untuk membeli paket data (quota) dari provider. Pilihan metode pelaksanaan KBM online dan yang terkait dengan hal tersebut perlu menjadi pertimbangan pihak yang berkompeten akan pencapaian LO KBM online di prodi TMP.
KBM Online Pada Masa New Normal
Masa kenormalan baru (new normal) disepakati sebagai masa dimana diartikan suatu kondisi dan/atau kebiasaan sosial masyarakat atau perilaku individu yang muncul setelah covid-19 selesai. Kondisi ini diharapkan tidak membuat masyarakat sosial menjadi kelompok baru yang kehilangan sosialnya yang lama [6]. Normal Baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi covid-19 yang belum selesai. Kenormalan Baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan selama Covid-19. New normal
New Normal, Kajian Multidisiplin | 143
merupakan hidup berdampingan dengan Covid-19, sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada 28 Mei 2020. "New normal adalah perubahan budaya, yaitu perubahan kebiasaan dalam keseharian terutama terkait dengan pandemi Covid-19. Selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dan seterusnya," ujar Yuri, seperti dikutip dari Kompas.com.
Kehidupan normal baru (new normal), adalah hidup berdampingan dengan Covid-19, berarti suatu Protokol menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Pemerintah menyebutnya ‘Penyesuaian PSBB’, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya serta menentukan bagaimana penyesuaian PSBB diberlakukan. Monoarfa menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada beberapa prasyarat agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin, yaitu: 1)penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB; 2)Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona; 3)Penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 4)Review pelaksanaan penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas. Dalam rilis pers tersebut diuraikan juga tentang kesulitan pemerintah memberlakukan pembatasan sepenuhnya, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2020 sudah menunjukkan kinerja menurun di 2,97 persen [7].
Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang normal baru sedini dan semasif mungkin, setidaknya sampai vaksin dan obat Covid-19 tersedia atau kasus Covid-19 dapat ditekan menjadi sangat kecil. Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan disiplin yang ketat dalam setiap kegiatan sehari-hari. Monoarfa menyampaikan bahwa Indonesia berpatokan pada tiga kriteria yang direkomendasikan WHO dalam membuat keputusan Penyesuaian PSBB. Kriteria pertama adalah epidemiologi, yaitu Angka Reproduksi Efektif (Rt) menunjukkan rata-rata jumlah orang yang terinfeksi oleh satu orang yang terinfeksi. Ketika Rt=2,5 berarti satu orang yang terinfeksi dapat
144 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menularkan virus ke 2-3 orang lainnya. Diharapkan Rt<1 selama dua minggu berturut-turut, artinya, walaupun virus masih ada tetapi penyebaran virus sudah dapat dikendalikan. Metode ini diadopsi berbagai negara, antara lain Amerika Serikat dan 54 negara bagiannya serta Inggris dan Jerman. Rt juga sangat dipengaruhi physical distancing.
Mengacu kepada hasil jajak pendapat terkait pelaksanaan KBM online prodi TMP terdapat dua permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar KBM online efektif dan efisien serta mencapai LO perkuliahan, yaitu terkait dengan alat/sarana yang digunakan untuk pelaksanaan KBM online dan pilihan metode perkuliahan yang dipakai dalam KBM online baik terutama untuk pelaksanaan praktikum. Upaya yang dilakukan prodi TMP dalam melaksanakan KBM online di masa new normal yang memiliki hambatan sinyal hilang dan labil agar tetap produktif, tetap sehat sesuai protokol kesehatan dan menyiapkan metode perkuliahan online yang sesuai dengan situasi kondisi mahasiswa TMP sehingga LO tercapai secara efektif, dapat dilakukan berdasarkan penjelasan berikut. Metode KBM di prodi TMP sebelum pandemi Covid-19 dirancang secara offline terutama untuk mata kuliah-mata kuliah yang melatih ketrampilan motorik baik saat penjelasan teori di kuliah maupun praktikum. Situasi dan kondisi mengharuskan prodi TMP merubah metode KBM yang semula offline menjadi online.
Berdasarkan hasil penelitian [8] bahwa setiap sistem sekolah harus moderat dengan teknologi yang memungkinkan mereka belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Teknologi Informasi (TI) adalah kunci untuk model sekolah masa depan yang lebih baik. Upaya anak-anak bangsa juga terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam hal menyampaikan proses pendidikan dengan meng-gunakan IT. Teknologi yang memanfaatkan ISDN (Integrated Sevices Digital Network) dapat digunakan untuk memfasilitasi teleconference sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh, dalam hal ini KBM online. TI dan Internet memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TI dan Internet tidak dapat digunakan secara optimal. Kesiapan pemerintah Indonesia masih dipertanyakan dalam hal ini. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukumnya yang mengaturnya. Infra-struktur hukum yang melandasi operasional pendidikan di Indonesia cukup memadai untuk menampung perkembangan baru berupa penerapan IT untuk pendidikan ini. Selain itu masih terdapat kekurangan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 145
pada hal pengadaan infrastruktur teknologi telekomunikasi, multimedia dan informasi yang merupakan prasyarat terselenggaranya IT untuk pendidikan sementara penetrasi komputer (PC) di Indonesia masih rendah.
Tempat akses internet dapat diperlebar jangkauannya melalui fasilitas di kampus, sekolahan, dan bahkan melalui warung Internet. Hal ini tentunya dihadapkan kembali kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta; walaupun pada akhirnya terpulang juga kepada peme-rintah. Penelitian [9] tentang Implementasi Teknologi Internet sebagai Solusi Pengentasan Masalah Komunikasi di Desa Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, menyimpulkan bahwa implementasi teknologi internet yang ada di Desa Nyamuk dapat membantu mengentaskan masalah ketertinggalan akses komunikasi, informasi, dan pendidikan di Desa Nyamuk. Hal ini salah satu solusi untuk keter-tinggalan akses komunikasi informasi dan pendidikan di wilayah pedesaan dapat di dengan penggunaan internet.
Berdasarkan hambatan yang terjadi saat kegiatan KBM online khususnya di lokasi tempat tinggal dosen dan mahasiswa prodi TMP maka untuk efektivitas pencapaian hasil pembelajaran setiap mata kuliah baik teori maupun praktikum maka perlu disiapkan dan diplih metode kegiatan KBM online yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Hasil penelitian [3] bahwa prestasi akademik mahasiswa sebesar 10,24% dan 89,76% di pengaruhi oleh faktor lain di luar kuliah online sebaiknya menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan hasil survey bahwa kondisi sinyal di tempat tinggal mahasiswa prodi TMP. Implementasi teknologi internet yang ada di Desa Nyamuk dapat membantu meng-entaskan masalah ketertinggalan akses komunikasi, informasi, dan pendidikan di Desa Nyamuk. Terdapat dampak positif dan negatif yang harus dikondisikan dengan kerja sama antar warga yang bersangkutan dan pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat harus diselesaikan dengan penanaman wawasan dan pengetahuan. Jaringan internet gratis di Desa Nyamuk diharapkan menjadi program berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat [9].
TI dan Internet memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TI dan Internet tidak dapat digunakan secara optimal. Selain kekurangan pada pengadaan infra-struktur teknologi telekomunikasi itu, multimedia dan informasi yang merupakan prasyarat terselenggaranya IT untuk pendidikan sementara penetrasi komputer (PC) di Indonesia masih rendah. Sementara itu
146 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tempat akses internet dapat diperlebar jangkauannya melalui fasilitas di kampus, sekolahan, dan bahkan melalui warung Internet. Hal ini tentunya dihadapkan kembali kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta; walaupun pada akhirnya terpulang juga kepada pemerintah. Sebab pemerintahlah yang dapat menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi investasi swasta di bidang pendidikan. Pengujian coverage area WLAN indoor menggunakan model COST-231 multiwall indoor menghasilkan kesimpulan bahwa jenis material dalam suatu area menjadi variabel atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kuat sinyal wireless dari suatu access point [10].
Mengacu kepada paparan di atas, maka salah satu alternatif solusi dari permasalahan sinyal labil dan atau sinyal hilang dengan cara merakit suatu alat penguat sinyal. Proses KBM online dengan penguat sinyal seperti dipaparkan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan learning outcome mata kuliah dapat dicapai. Alat penguat sinyal HP ini terdiri dari: booster, antene luar dan dalam, adaptor, klem, kabel dan alat pelindung antene luar berupa kotak penutup. Kerja alat penguat sinyal ini ditentukan oleh frekwensi booster yang dipengaruhi oleh jenis HP/smartphone, jenis SIM card, provider yang dipilih untuk HP tersebut. Saat ini yang sudah ada di pasaran online adalah booster untuk sim card telkomsel 3G dengan frekwensi 1800-2100 MHz. Alat penguat sinyal yang dirakit harus berbeda dengan yang sudah ada saat ini, yaitu. perbedaan frekwensi dari yang sudah ada, disesuaikan dengan jenis HP, sim card dan provider yang ada di wilayah domisili mahasiswa. Sehingga hasil rakitan alat penguat sinyal tersebut dapat digunakan oleh beragam jenis HP dengan simcard dan provider yang berbeda sesuai dengan frekwensi masing-masing.
Dampak sosial alat penguat sinyal ini dalam jangka panjang diharapkan dapat dipakai di seluruh Indonesia tidak hanya oleh maha-siswa Sekolah Vokasi IPB khususnya program studi TIB dan TMP yang berdomisili pada wilayah-wilayah dimana jajak pendapat sederhana dilaksanakan tetapi juga dapat digunakan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan, seperti: masyarakat desa terpencil, petani. Petugas peme-rintah, petugas kesehatan di wilayah terpencil, nelayan ataupun masyarakat pinggiran lain yang memerlukan alat penguat sinyal pada HP nya. Perakitan alat penguat sinyal ini secara teknis dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan cara memperoleh data pengguna terbanyak simcard dan provider HP. Selanjutnya dilihat frekwensi dari provider terbanyak yang digunakan di wilayah tersebut. Perakitan alat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 147
disesuaikan dengan data frekwensi yang dimiliki. Perakitan alat penguat sinyal ini juga dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bagian barat, tengah, dan timur, sehingga masalah terkait hilang dan labil sinyal dapat teratasi.
Penelitian [8] menjelaskan bahwa media komunikasi internet, bersifat dapat dihubungi kapan saja, itu berarti siswa dapat meman-faatkan program pendidikan yang disediakan di internet kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka, sehingga ruang dan kendala waktu yang mereka hadapi dalam menemukan sumber belajar dapat diatasi. Berbagai kemungkinan untuk pengembangan dan penerapan TI untuk pendidikan bisa terjadi termasuk kondisi sinyal hilang dan kurang stabil tersebut mengingat penggunaan TI di Indonesia baru saja memasuki tahap mempelajari. Informasi yang diwakili oleh komputer yang terhu-bung ke internet sebagai media utama telah mampu memberikan kontribusi yang begitu besar bagi proses pendidikan. Teknologi interaktif ini menyediakan dorongan untuk transformasi pasar menuju peran guru: dari informasi menjadi transformasi. Setiap sistem sekolah harus moderat dengan teknologi yang memungkinkan mereka belajar lebih cepat, lebih baik, dan lebih pintar. Teknologi Informasi adalah kunci untuk model sekolah masa depan yang lebih baik
Tahapan kegiatan perakitan alat penguat sinyal, secara teknis terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 1). pra perakitan, 2). proses perakitan, dan 3). pasca perakitan. Kegiatan yang dilakukan pada pra kegiatan perakitan adalah menentukan sim card dan provider yang terbanyak digunakan untuk HP, kegiatan ini diperlukan untuk menentukan frekwensi yang sesuai untuk alat penguat sinyal, termasuk pembelian alat. Proses perakitan alat penguat sinyal terdiri atas 2 tahapan, yaitu: sinkronisasi antara frekwensi-frekwensi dari provider dengan alat penguat sinyal, kemudian menempatkan alat di tempat yang sesuai dan aman serta disesuaikan dengan daya listrik yang tersedia. Kegiatan pasca perakitan alat penguat sinyal merupakan pengujian kekuatan sinyal setelah penggunaan alat penguat sinyal, apakah sinyal yang ada sudah tertangkap HP atau belum. Kegiatan seluruh tahapan kegiatan perakitan direncanakan selama 10 hari [11].
Pilihan metode perkuliahan yang dipakai dalam KBM online baik terutama untuk pelaksanaan praktikum menentukan pencapaian LO mata kuliah. Kreativitas seorang dosen untuk menuangkan materi perku-liahan ke dalam bentuk audio visual/tayangan video dan ditayangkan secara online hingga materi tersebut difahami dan dimengerti oleh
148 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mahasiswa. KBM online disusun secara kolaborasi antara bidang ilmu yang terkait dengan prodi TMP juga dengan bidang ilmu informatika dalam hal ini prodi Informatika. Kolaborasi ini membentuk suatu tim dosen yang terdiri atas kompetensi yang memuat substansi topik yang disampaikan pada perkuliahan dan kompetensi daring dalam memilih metode perkuliahan daring [11]. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan suatu modul kuliah yang menjadikan perkuliahan online menjadi nyaman, menyenangkan dan mahasiswa memahami materi yang disampaikan dosen sehingga terjadi efektivitas pencapaian LO mata kuliah yang disampaikan.
Rujukan
[1] Anonim, Buku Panduan The New Normal. PT. Gapura Angkasa. Management of PT Gapura Angkasa., 2020.
[2] M. I. Mustofa, M. Chodzirin, L. Sayekti, and R. Fauzan, “Formulasi Model Perkuliahan Daring Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi,” Walisongo J. Inf. Technol., vol. 1, no. 2, p. 151, 2019, doi: 10.21580/wjit.2019.1.2.4067.
[3] R. Adibowo and T. Fidowaty, “Pengaruh Efektivitas Kuliah Online Dalam Website Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Unikom,” J. Ilmu Polit. Komunikasi., vol. III No, 1, no. 1, pp. 71–87, 2013, [Online]. Available: https://repository.unikom.ac.id/ 30680/1/5-jipsi-unikom.pdf.
[4] E. Karwati, “Pengaruh Pembelajaran Elektronik (E-Learning) terhadap Mutu Belajar Mahasiswa,” J. Penelit. Komun., vol. 17, no. 1, pp. 41–54, 2014, doi: 10.20422/jpk.v17i1.5.
[5] M. Lamina, “Analisis Penerimaan Sinyal Ponsel Pada Sistem Komunikasi Selular,” J. Tek. Elektro Univ. Tanjung Pura., vol. 1 No 1, pp. 1–8, 1800, [Online]. Available: http://jurnal. untan.ac.id/index.php/jteuntan/article/view/3934
[6] A. Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19,” Journal.Uinjkt.Ac.Id, vol. 4, no. 1, pp. 197–202, 2020, doi: 10.15408/adalah.v4i1.15809.
[7] TIM Penulis UNAIR, Menjaga Nalar Mencari Jalan Keluar Dari Pandemi COVID_19. Urun Rembug Universitas Airlangga. . Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Gedung Rektorat Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
[8] Y. Pujilestari, “Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19,” Adalah, vol. 4, no. 1, pp. 49–56, 2020, [Online]. Available: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/1539
New Normal, Kajian Multidisiplin | 149
4/7199. [9] B. A. A. Sumbodo, A. Dharmawan, and F. Faizah, “Implementasi
Teknologi Internet Sebagai Solusi Pengentasan Masalah Komunikasi di Desa Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. (Indonesian J. Community Engag., vol. 2, no. 2, pp. 189–203, 2017, doi: 10.22146/jpkm.15654.
[10] Y. Ardian, “Analisis Jenis Material Terhadap Jumlah Kuat Sinyal Wireless Lan Menggunakan Metode Cost-231 Multiwall Indoor,” Matrix J. Manaj. Teknol. dan Inform., vol. 7, no. 3, p. 68, 2017, doi: 10.31940/matrix.v7i3.608.
[11] L. Dahliani, Kapita Selekta Manajemen dan Agribisnis Perkebunan. Bogor: IPB Press Printing, 2019.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 151
Bab 11
Pandemic COVID 19 Mengembalikan Pendidikan dalam Keluarga Munawir Pasaribu 12
Pengantar
Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh segenap orang, bahkan dengan pendidikan inilah nantinya kualitas seorang akan bisa dilihat. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi berkembanganya keberadaban manusia [1] .
Pendidikan haruslah diberikan kepada orang yang mampu mengelolanya dengan baik terutama harus diberikan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani. Terkhusus kepada peserta didik untuk mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaaanya (baik se-bagai Khalifutullah fil al-ardh maupun sebagai abd Allah ) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam [2]. Orang yang bertanggung jawab ini merupakan orang yang sangat berjasa dalam perkembangan jasmani dan rohani para anak didik itulah yang sering disebut dengan guru.
Sekarang dunia pendidikan sedang diuji dengan ujian yang begitu berat. Terjadinya pandemic yang telah menggguncang dunia membuat dunia pendidikan porak-poranda. Bahkan hampir dipastikan tidak ada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini yang tidak terkena imbas dari pandemic Covid 19 ini, bahkan jika dilihat secara global hampir semua negera di dunia ini mempunyai dampak yang begitu mengkhawatirkan. Jika dilihat rilis dari media massa dan juga elektronik dan juga dari beberapa hasil penelitian-penelitian yang telah di publish megungkapkan bahwa COVID-19 memiliki efek buruk pada pendidikan, termasuk gangguan belajar, dan penurunan akses ke fasilitas pendidikan dan penelitian, kehilangan pekerjaan dan peningkatan hutang siswa terhadap lembaga pendidikan yang ditempuhnya [3].
Pandemic Covid 19 yang telah melanda semua Negara termasuk Indonesia, membuat pemerintah melakukan berbagai macam terobosan dan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, salah satunya dilakukan WFH yaitu semua harus dilakukan dirumah. Ketika
12 Dr. Munawir Pasaribu. Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
152 | New Normal, Kajian Multidisiplin
kebijakan ini dilakukan disemua lini termasuk di dalam dunia pendidikan maka membuat permasalahan yang begitu berat terhadap pengelola pendidikan, ditambah lagi kebijakan yang di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengganti sistem pendidikan yang awalnya konvensional tatap muka dengan kebijakan baru yaitu sistem belajar daring.
Melihat perkembangan terpaparnya virus COVID 19 di Indonesia semakin meningkat pemerintahan Indonesia melalui menteri Pendidikan dan Kebudaya mengeluarkan surat edaran no 4 tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Jika dilihat secara keseluruhan terdapat 6 poin yang sangat urgent di dalam surat edaran tersebut mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan pendidikan yang harus disikapi oleh kepala sekolah,guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, yaitu 1) Pelaksanaan Ujian Nasional, 2) Proses Belajar dari Rumah, 3) Ujian Sekolah, 4) Kenaikan Kelas, 5) Penerimaan Peserta Didik Baru, dan 6). Dana Bantuan Operasional Sekolah (Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 1 9), 2020)
Ketika pembelajaran online terjadi berarti semua pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing. Bagi yang punya anak yang masih bersekolah maka orang tua tidak dapat mengelak lagi untuk membimbing anaknya di rumah karena sekolah tempat anaknya biasa belajar untuk sementara waktu ditutup yang belum ada waktu yang jelas belajar dengan normal dilakukan di sekolah.
Pandemic COVID 19 yang telah membuat permasalah begitu besar terhadap pendidikan mengingatkan bahwa begitu pentingnya pendidik-an di dalam keluarga. Sekarang ini orang tua, baik itu Ayah dan Ibu di rumah merupakan pendidik yang utama yang akan anak-anak rasakan ketika melakukan pembelajaran di rumah. Melihat permasalahan ini mampukah orang tua mendidik anaknya di rumah dan sejauh mana pendidikan yang dilakukan di rumah mampu membuat anak-anak akan terisi perkembagan jasmani dan rohaninya.
Pembahasan
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kesalamatan. Ada beberapa macam menjaga keselamatan ini, ada dengan cara diam saja dan ada juga menjaga lisannya. Dalam sejarah, para ahli terutama sekali dokter mendeskrifsikan wabah-wabah yang terjadi dalam tinjauan medis, lalu dicarikan solusi dan penanganannya secara medis pula. Hal
New Normal, Kajian Multidisiplin | 153
ini menginisiasi munculnya teknik-teknik pengobatan dan obat-obatan yang relevan untuk penyakit terutama wabah tersebut.
Para ahli agama mengatakan bahwa jika terjangkit dengan penyakit atau wabah senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istikhfar, sabar, dan ridha menerima ketetapan Allah tersebut. Karena itu semuanya terjadi dikarenakan kehendak Allah swt. Jika kita mengkaji dalam pendidikan dan hadis-hadis banyak naskah-naskah yang mengatakan bahwa untuk menjaga keselamatan dari bahaya wabah maka cukup berdiam diri di rumah istilah inilah dalam dunia kedokteran dikatakan dengan lockdown [5].
Terjadinya lockdown dan mengakibatkan semua pekerjaan dilakukan dirumah membuat dalam hitungan singkat, manusia ketakutan keluar rumah dikarenakan virus yang mengintai diluar rumah bisa saja memakan korban dengan resiko yang tidak main-main yaitu kematian yang begitu cepat. Wabah Virus Korona juga mengharuskan agar setiap orang menjaga jarak (physical distancing), memakai masker, jika keluar dari kota mengakibatkan karantina, isolasi mandiri dan bahkan sebahagian kota-kota besar melakukan kebijakan yang lebih luas lagi dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Permasalahan ini mengakibatkan dampak yang begitu besar yang menyentuh semua sisi kehidupan. Seluruh umat manusia di dunia, termasuk di Negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung ikut merasakannya. Anak-anak dan remaja tidak hanya menjadi yang rentan tertular Virus COVID 19 ini, tetapi mereka juga termasuk di antara korban pada efek yang lain, salah satunya pendidikan. Jika dilihat dunia pendidikan terutama sekali dari umur 4 -5 tahun ada yang bersekolah di PAUD dan TK yang murid-muridanya sama sekali belum mengerti dengan kesehatan dan belum bisa bertahan memakai masker berlam-lama.
Menurut data dari UNICEF ada 99 persen anak-anak dan remaja di bawah delapan belas tahun di seluruh dunia (2,34 miliar) yang tinggal di 186 negara dengan beberapa bentuk pembatasan gerakan yang berlaku karena Virus COVID 19. Enam puluh persen anak tinggal di salah satu dari 82 negara dengan kebijakan Negara sedang melakukan lockdown termasuk juga di Negara Indonesia [6]. Jika dilihat dari data statistik kemendikbud jumlah sekolah dan peserta didik ditahun akademik 2019/2020 ini berjumlah 169.378 sekolah negeri dan 138.277 sekolah swasta serta peserta didik 25,203,371 siswa [7]. Melihat data dari kemendikbud ini begitu besar potensi penyebaran COVID 19 jika
154 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pemerintah tidak mengambil langkah dan menetapkan kebijakan meliburkan sekolah dan diganti dengan belajar dari rumah.
Pendemik COVID 19 yang melanda semua penjuru dunia tidaklah melailaikan kita dari belajar. Pendidikan harus terus dijalankan, yang menanggung jawabi pendidikan ini bukan saja pemerintah, organisasi, atau masyarakat umum namun setiap orang mempunyai kewajiban bersama dalam proses pelaksanaan pendidikan, baik sebagi guru, peserta didik, memberikan informasi kepada orang lain tentang ilmu dan pendidikan itu sendiri semua harus berkerjasama dan bertanggung jawab.
Pembelajaran online yang dilaksanakan dari rumah sebahagian orang banyak yang mengatakan jadi permasalahanan yang besar, dan ada juga sebahagian guru dan orang tua murid mengambil hikmah dari pembelajaran dari rumah ini. Guru banyak mengatakan jadi pintar teknologi sehingga tidak gaptek lagi, ada juga mengatakan guru harus punya model pembelajaran baru, pembuatan modul pembelajaran dan juga guru harus kreatif memberikan materi pembelajaran dalam berbagai situasi yang ada.
Sementara di lingkungan keluarga banyak yang menyampaikan inilah saatnya kembali ke keluarga memerankan peranan yang semesti-nya yang dilakukan kedua orang tua bahwa, tugas orang tua bukan saja memberikan kebutuhan fisik dan material berupa sandang, pangan dan papan saja namun juga orang tua harus mampu memberikan didikan kepada anaknya baik memberikan pengarahan langsung, sebagai uswah hasanah kepada anak dan juga pembimbingan dalam pelajaran di sekolahnya.
Dalam kontek kekinian dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberi pengaruh terhadap per-kembangan sosial, terutama guru, orang tua dan peserta didik. Pengaruh kelompok sosial yang pertama-tama dihadapi manusia sejak dilahirkan, yaitu kelompok keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Pengaruh dominan yaitu distorsi terhadap waktu penjadualan kegiatan pembelajaran peserta didik, baik secara struktur, pembagian tugas dan internalisasi norma-norma. Peran yang selama ini dilaksanakan di satuan pendidikan beralih fungsi di satuan keluarga [8].
Pelaksanaan pendidikan di rumah melalui online yang semakin hari semakin membosankan para orang tua dan anak-anak kembali
New Normal, Kajian Multidisiplin | 155
menjadi beban pemikiran pemerintah di negara ini. Sehingga membuat sebuah kesepakatan bersama oleh 4 menteri di negara ini dengan mengeluarkan sebuah Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Yang membagi pelaksanaan pembelajaran dengan beberapa zona yaitu satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Kuning, Oranye, dan Merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam.
Sementara daerah yang mempunyai ketetapan dengan zona hijau Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewe-nangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap (Kemendikbud, 2020).
Walaupun ada kewenangan yang diberikan pemerintah dan pebagian zona ditiap daerah, bagi daerah zona hijau masih bisa melakukan tatap muka namun dengan protokol kesehatan yang ketat bagi satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap warga sekolah dan juga warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, peserta didik yang telah disiapkan protokol kesehatan wajib mengikuti protokol kesehatan tersebut.
156 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Permasalahan dilapangan sangat berbeda didapatkan, bahwa
sekarang ini hampir keseluruhan daerah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia tidak ada lagi daerahnya yang statusnya zona hijau melainkan hampir semua daerah kabupaten kota tersebut sudah terkena zona merah sehingga kewenangan pemerintah dalam melaksanakan proses pendidikan bagi daerah zona hijau tetap tidak bisa dipergunakan sehingga dipastikan seluruh peserta didik tetap melaksanakan proses pembelajaran melalui daring (online).
Pandemi COVID-19 telah mengganggu kehidupan para siswa dengan berbagai cara, semua jenjang tingkatan sekolah terkena imbasnya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi. Banyak para pelajar tidak bisa menyelesaikan pembelajarannya secara baik. Dikarenakan pembelajaran dilakukan hanya dengan online sehingga pembelajaran dalam bentuk praktek dan memakai laboratorium tidak dapat dilaksanakan.
Melihat begitu kompleksnya permasalahan dalam pembelajaran dikarenakan COVID 19 ini sehingga membuat pertanyaan mendasarkan, bagaimanakah bentuk kurikulum yang akan dijalankan ketika pandemi COVID 19 ini? Apakah kurikulum akan dirubah atau kurikulum dibuat secara tematis atau kebijaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan keper-luan dalam masa COVID ini. Inilah yang akan menjadi tantangan dan pekerjaan berat untuk pemangku kebijakan yaitu pemerintahan dan juga para guru pendidik di sekolah dalam menjalakan pendidikan secara online di masa pendemik ini.
Pandemik COVID 19 belum ada yang bisa memprediksi kapan bisa berakhir, sehingga membuat kekhawatiran serta kecemasan yang tinggi oleh para siswa dan orang tua murid kapan pembelajaran di sekolah kembali normal. Bahkan ketika lembaga pendidikan membuat perubahan yang diperlukan untuk mengajar dengan cara yang berbeda, semua harus memberikan prioritas tertinggi untuk meyakinkan siswa dan orang tua bahwa proses dari hasil belajar anak didiknya sesuai dengan target yang sudah dicapai oleh sekolah. Pengelola pendidikan harus memberikan informasi baru sesering mungkin kepada siswa dan orang tua sehingga tidak menimbulkan permasalahan dibelakang hari yang akan datang.
Guru di sekolah mungkin lebih baik dari pada orang tua dalam memberikan informasi langsung tentang apa yang mereka pelajari dan juga guru lebih baik memberikan pembinaan emosi dan pembinaan mental kepada anak didik. Sayangnya, keharusan saat ini untuk melanjut-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 157
kan sekolah dengan transisi cepat ke pembelajaran jarak jauh mungkin memiliki dampak yang berlawanan. Guru serta pengelola pendidikan dan sistem pendidikan harus melakukan upaya khusus untuk membantu siswa yang orang tuanya tidak mendukung lingkungan rumahnya sehingga bisa kondusif untuk belajar. Ketika rumah tangga terbatas pada tempat tinggal mereka oleh COVID-19, orang tua dan wali mungkin sangat cemas tentang masa depan ekonomi mereka sendiri, sehingga belajar di rumah tidak mudah, terutama untuk anak-anak dengan moti-vasi rendah. Rumah-rumah seperti itu seringkali kekurangan peralatan dan konektivitas seperti peralatan listrik , smartphone, jaringan internet yang stabil, dan ini sangat berbeda dari mereka yang mempunyai rumah yang serba cukup dan keluaga yang kaya [10].
Semua orang yang ada dipermukaan bumi ini pasti jika ditanya mereka tidak akan mau mengalami keadaan seperti sekarang ini, pem-belajaran secara online, pembatasan gerak di sekolah, tidak dapatnya melaksanakan praktek dikarenakan bisa membuat kumpulan orang banyak bahkan kurangnya praktek langsung di laboratorium, namun karena pandemik ini tidak bisa ditolak karena sudah mewabah maka harapan kita dalam keadaan apapun pendidikan harus terus dijalankan namun menyesuaikan pedoman protokol kesehatan yang ada.
Pendidikan dalam Keluarga
Dampak COVID 19 ini mengakibat belajar di rumah secara online. Tambahnya di era globalisasi ini dipastikan memiliki tantangan dan menghadapi beragam persoalan dan perubahan sosial yang tidak dapat di prediksi. Dalam Islam mengenai pendidikan keluarga sudah diatur melalui Alquran dan sunnah Nabi. Dalam Alquran jelas Allah menyam-paikan Peliharalah dirimu dan keluargamu dari kobaran api Neraka (Qs : At-Tahrim 6). Ada sebuah ungkapan yang bagus mengingatkan bagaimana menghidupkan rumah seperti layaknya sebuah surga dengan ungkapan Rumahku adalah Surgaku. Bahkan jika kita telusuri lagi hadis-hadis Nabi saw tentang di rumah ini bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam pembentukan kepribadian anak di rumah. Seperti salah satu hadis Nabi Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Tidak ada dari seorang anak (adam) melainkan dilahirkan dari dasar fitrah (Islam), maka kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama Yahudi dan Nasrani atau beragama Majusi (HR. Muttafaq ‘Alaih).
Hadis Nabi ini memberikan keterangan bahwa yang membentuk fitrah manusia dari awal itu adalah kedua orang tuanya, maka orang tualah yang memberikan informasi kepada anak, mau dijadikan apa anak
158 | New Normal, Kajian Multidisiplin
itu apakah Yahudi, Nasrani dan Majusi, dalam kontek inilah pendidikan dari keluarga sangatlah penting dalam menjaga akidah anak [12]. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak, anak dipandang sebagai suatu tabula rasa (kertas putih) dimana orang tualah yang akan bertanggung jawab mendidik, mengembangkan dan memben-tuk karakter anak tersebut [13]. Jika diperhatikan hadis tersebut menunjukkan bahwa kesholehan orang tua sangat dituntut dalam membentuk keturunan (anak-anak) yang baik.
Orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak yang sering melihat orang tuanya beribadah kepada Allah seperti berzikir, membaca quran, bersedekah, mengerjakan sholat-sholat sunnah maka sianak in Sya Allah akan meniru dari orang tuanya. Islam merupakan ajaran yang sangat memperhatikan anak dan perkem-bangannya. Zakiyah derajar mengungkapkan bahwa karena orangtua merupakan pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berke-nalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi dan pemikirannya kelak, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua yang di lihatnya dahulu [14].
Keluarga merupakan asal dari kata bahasa Indonesia jika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu :1). Ibu dan bapak berserta anak-anaknya seisi rumah; 2). Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung jawab batin; 3). Sanak saudara kaum kerabat [15]. Pengertian keluarga menurut pimpinan Pusat Aisyiyah adalah orang seisi rumah, terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu dari orang tua (ayah atau Ibu) beserta ataupun tanpa anak-anak dapat juga berupa anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu keluarga tersebut [16]. Jika disederhanakan pengertian secara keseluruhan keluarga itu adalah sebuah kumpulan Ibu, bapak, anak-anak serta kaum kerabat yang terkumpul dalam sebuah rumah.
Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dan bahkan anak pertama sekali mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarganya. Cakupan makna “pertama dan utama” tidak hanya dalam dimensi waktu atau kronologis proses terjadinya pen-didikan namun juga dalam dimensi tanggung jawab. Keluarga diharap-kan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh men-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 159
jadi pribadi, serta mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan. Keluarga adalah sebagai kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama dan bersifat alamiah. Dalam keluarga, anak dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangan-nya sebagai bekal ketika memasuki dunia orang dewasa, bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan, seharusnya menjadi tugas yang dikerjakan keluarga dan masyarakat di dalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga [17].
Keluarga menduduki posisi terpenting di antara lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. Biasanya dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama untuk membentuk perilaku anak. Karena porsi pendidikan agama di sekolah belum mencukupi di dapatkan oleh anak didik. Oleh karena itu, pen-didikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan suara hatinya. Semen-tara saat ini lain lagi permasalahannya bahwa semua mata pelajaran harus diketahui oleh orang tua dikarekan sistem pembelajarannya dilakukan dengan online. Betapapun proses pendidikan telah diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal, secara sosio-historis kehadiran lembaga-lembaga pendidikan profesional itu merupakan pengganti peran atas peran lembaga keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama tadi. Dengan demikian jelas dapat dikatakan lembaga pendidikan profesional itu menerima mandat dari lembaga keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan bagi para anggota keluarga.
Terkadang keluarga terjebak dengan pemikiran bahwa pendidikan yang mantap dan bagus itu jika anak dimasukkan kedalam sebuah sekolah yang terbaik dan favorit yang mempuyai segudang prestasi dan nilai-nilai akademiknya bagus serta lulusnya menjadi terbaik. Akan tetapi terkadang abai dari perilaku yang mempunyai akhlak yang baik, sopan santun dan ibadah yang tekun, sehingga orang tua tidak lagi mengontrol anaknya jika sampai di rumah.
Dalam berbagai literatur, para ahli memberikan berbagai sudut pandang tentang pengertian pendidikan keluarga. Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang bapak pendidikan Indonesia, juga menyatakan bahwa permulaan dalam alam pendidikan adalah alam keluarga bagi
160 | New Normal, Kajian Multidisiplin
setiap orang yang baru lahir. Orang tualah (ayah maupun ibu) Untuk pertama kalinya, berkedudukan sebagai penuntun (guru), sebagai pengajar, sebagai pendidik, pembimbing dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak. [18]. Berbagai macam penafsiran para ahli tentang membicarakan pendidikan keluarga, yang pada intinya adalah pendidikan keluarga merupakan sebuah proses pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai pijakan fondasi awal dalam pendidikan, segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak untuk diberi tanggung jawab berupa nilai-nilai, akhlak, keteladanan dan kefitrahan [19]–[21]. Maka tidak berlebihan kiranya manakala merujuk pada pendapat para ahli di atas konsep pendidikan keluarga. Tidak hanya sekedar tindakan (proses), tetapi ia hadir dalam praktek dan implementasi, yang dilaksanakan orang tua (ayah-ibu) degan nilai pendidikan pada keluarga [22].
Organisasi besar seperti Muhammadiyah sendiri mengeluarkan sebuah Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang salah satu pembahasannya disitu ada tentang keluarga. Dalam PHIWM ini dalam bagian ketiga dalam point B menjelasakan tentang Kehidupan dalam Keluarga poin tentang Kedudukan Keluarga menjelaskan bahwa Pertama Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang dikenal dengan Keluarga Sakinah. Kedua Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewu-judkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama’ah dan da'wah Jama’ah menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya [23].
Pada hakikatnya, fungsi keluarga adalah sebagai pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, pembentukan kebiasaan dan pen-didikan intelektual anak. Fungsi keluarga setidaknya ada tiga dalam pendidikan anak, yaitu, 1). Fungsi kuantitatif, yaitu menyediakan bagi pembentukan perilaku dasar, artinya keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar fisik anak, berupa pakaian, makanan dan minuman, serta tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, keluarga dituntut untuk menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan dasar-dasar kebaikan, berupa perilaku, etika, sopan santun dan pembentukan karakter anak yang santun dan berakhlak baik sebagai fitrah manusia yang hakiki; 2).
New Normal, Kajian Multidisiplin | 161
Fungsi selektif, yaitu menyaring pengalaman anak dan ketidaksamaan posisi kemasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya pendidikan keluarga berfungsi sekaligus memerankan diri sebagai fungsi kontrol pengawasan terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima anak. Terutama anak usia 0 tahun hingga 5 tahun yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman. Sehingga diharapkan mampu membeda-kan mana yang baik dan buruk. Oleh sebab itu, keluarga (ayah dan ibu) berkewajiban memberikan informasi dan pengalaman yang bermakna. Berupa pengalaman belajar secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan pengalaman tersebut mampu diserap dan ditransformasi dalam diri anak; 3) Fungsi pedagogis, yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma- norma. Artinya pendidikan keluarga berfungsi memberikan warisan nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek kepribadian anak.
Mengacu pada makna keluarga dalam konteks sosiokultural Indonesia pada khususnya, diketahui bahwa keluarga memiliki fungsi-fungsi : 1). Sebagai persekutuan primer, yaitu hubungan antara anggota keluarga bersifat mendasar dan eksklusif karena faktor ikatan biologis, ikatan hukum dan karena adanya kebersamaan dalam mempertahankan kehidupan; 2). Sebagai pemberi afeksi (kasih sayang) atas dasar ikatan biologis atau ikatan hukum yang didorong oleh rasa kewajiban dan tanggung jawab; 3). Sebagai lembaga pembentukan yang disebabkan faktor anutan, keyakinan, agama, nilai budaya, nilai moral, baik bersumber dari dalam keluarga maupun dari luar; 4). Sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat material maupun mental spiritual; 5). Sebagai lembaga partisipasi dari kelompok masyarakatnya, yaitu berinteraksi dalam berbagai aktivitas, baik dengan keluarga lain, masyarakat banyak maupun dengan lingkungan alam sekitarnya.
Sementara itu, ternyata fungsi keluarga bukan hanya sebatas itu namun, tugas akhir pendidikan keluarga tercermin dari sikap, perilaku dan kepribadian (personality) anak dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan. Pendidikan keluarga bukanlah pendidikan yang diorgani-sasikan, tetapi pendidikan yang ‘organik’ yang didasarkan pada ‘spontanitas’, intuisi, pembiasaan dan improvisasi.
Ada beberapa aspek dalam pembinaan keluarga terkhususnya dalam pendidikan yang antara lain adalah; 1). Menjadikan Madrasah keluarga sebagai aktualisasi potensi fitrah sejak kanak-kanak dengan memberikan kesempatan agar semua potensi kejiwaannya berkembang dari awal; 2). Memberikan perhatian dan kesungguhan terhadap pen-didikan anak; 3). Mensosialisasikan anak untuk mempunyai cita-cita
162 | New Normal, Kajian Multidisiplin
(impian besar) dan sering mengingatkannya; 4). Memilihkan dan mengarahkan anak pada pendidikan formal (sekolah) yang mampu mengembangkan intelektualnya dan kepribadian anak secara optimal khususnya kepribadian muslim ; 5). Mendorong anak untuk mempunyai motivasi yang tinggi dan berprestasi. Orang tua harus mampu meng-apresiasi prestasi anak ; 6). Mendorong dan memfasilitasi anak untuk berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, perjuangan dan orga-nisasi kepemudaan; 7). Mengusahakan pengadan perpustakaan keluarga ; 8). Menunjukkan peghormatan dan perlakuan yang ihsan kepada anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari peraktek-peraktek kekerasan dan penelantaran kehidupan anggota keluarga [16].
Harus diakui pembelajaran yang dilakukan di rumah memang tidak mudah dan gampang, ada beberapa faktor yang sangat parah yang didapatkan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya di rumah yaitu orang tua mengalami stres yang tinggi karena mengasuh anaknya. Faktor pengasuhan dalam keluarga adalah pendorong penting pertumbuhan dan perkembangan awal sehat anak-anak dan dengan demikian penting dalam menentukan keparahan dampak pandemi pada anak-anak muda sekarang dan di masa depan. Dalam situasi krisis, pengasuh utama dan orang tua berjuang untuk bersaing dengan menyediakan kesehatan, nutrisi, keamanan, dan perawatan anak. Bagi rumah tangga yang sudah hidup dalam kondisi kesulitan dan stres, krisis ini mungkin memiliki efek yang sangat berbahaya. Dan dengan banyaknya fasilitas peng-asuhan anak dan pendidikan dini yang ditutup di seluruh dunia, dan interaksi dengan keluarga besar terganggu, anak-anak kehilangan stimulasi sosial dan kognitif di luar rumah mereka [24].
Selain itu hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa hanya tiga dari sepuluh orang tua dapat menyesuaikan diri dengan peran sebagai pendidik bagi anak sendiri dan mampu menciptakan kenya-manan ketika memberikan pembelajaran pada anak di rumah. Tiga dari sepuluh orang tua mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para guru selama kegiatan pendidikan dari rumah. Kesepuluh orang tua menyatakan keprihatinannya dengan kondisi yang ada dan bersepakat bahwa peran guru tidak mudah untuk dijalani [25].
Wabah Coronavirus telah memaksa jutaan siswa untuk belajar dari rumah. Ini bukan fenomena baru karena rumah telah lama menjadi pusat pembelajaran terutama dalam hal pendidikan informal. Belajar dari rumah menjadi hal baru bagi siswa. Menurut tugas Pendidikan, sebagian besar para murid masih lebih suka belajar dan lebih nyamanan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 163
di rumah mereka sendiri karena peserta didik cenderung memiliki segalanya yang mereka miliki tanpa harus meninggalkan pembelajaran mereka. Namun, kenyataan menerima pendidikan formal dari rumah bisa sangat menantang bagi banyak pendidik, pelajar dan orang tua terutama di negara-negara berkembang di mana aksesibilitas, keter-sediaan, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak tersebar luas.
Terlepas dari biaya mengakses pendidikan online, banyak faktor lain seperti masalah jaringan, jaringan listrik yang buruk, gangguan, keterampilan digital yang buruk, tidak dapat diaksesnya dan masalah ketersediaan juga dapat menghambat kelancaran belajar dari rumah. Ada juga masalah waktu untuk mempelajari teknologi baru yang mungkin diperlukan untuk belajar dari rumah, dan suara-suara yang berasal secara internal atau eksternal dari para murid dan orang tua murid. Karena akses yang tidak merata ke teknologi masalah serius lainnya bagi banyak negara, penutupan sekolah yang lama dapat merampas jutaan siswa akses ke pendidikan terutama yang ada di negara dunia ketiga, daerah pedesaan, dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. UNESCO memahami tantangan ini, dan upaya yang dilakukan oleh mereka untuk membantu pendidik dan siswa di negara-negara yang terkena dampak untuk mengajar dan belajar secara online dari rumah mereka melalui penyediaan perangkat lunak gratis yang memfasilitasi pendidikan jarak jauh.
Apapun yang mendasari untuk membimbing anak belajar di rumah jika dilihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional mengatur tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 ayat satu mengatakan Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendi-dikan anaknya. Pasal dua Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya (Sisdiknas, 2003). Dalam seluruh naskah undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut peran orang tua sebagai penanggungjawab utama pendidikan anak seolah terabaikan, diganti dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Peran orang tua disebutkan “ber-hak” berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan “ber-hak” memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Seolah-olah pendidikan diselenggarakan oleh suatu pihak (baca: pemerintah) sedangkan orang tua adalah pihak yang berperan sebagai pihak ketiga. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan orang tua berke-
164 | New Normal, Kajian Multidisiplin
wajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, tanpa penjelasan lebih lanjut [28].
Pembinaan keluargan menjadi keluarga yang berkualitas dan mandiri merupakan tanggungjawab keluarga sendiri, masyarakat dan negara. Pemerintah sebagai pelaksana tanggungjawab negara berkewa-jiban menyiapkan relugasi dan fasilitas terlaksananya pembinaan keluarga.
Penutup
Pandemic COVID 19 yang melanda semua Negara haruslah semua memakluminya, karena tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi. Bagi selaku masyarakat yang belajar maka kewajiban melakukan pembelajaran walaupun dengan fasilitas yang terbatas serta keadaan yang memaksa. Oleh sebab itu mari bersama-sama mengem-balikan fungsi keluarga dalam kehidupan dengan cara memanfaatkan pandemic ini dengan rutin berkumpul dengan keluarga, memberikan pelajaran kepada anak-anak, mengontrol prilaku mereka, mengawasi apa yang mereka perbuat serta memberikan contoh keteladanan orang tua kepada anak anaknya.
Pandemic COVID 19 memaksa sistem pembelajaran mengguna-kan dengan daring. Jangan menyalahkan situasi namun, mari berbuat untuk menjadikan situasi ini lebih baik. Memberikan pengajaran kepada anak merupakan tugas pokok seorang orang tua di rumah. Alquran dan hadis-hadis Nabi menggambarkan betapa pentingnya peranan orang tua di rumah melihat tumbuh kembangnya seorang anak di rumah. Tokoh tokoh pendidikan juga mengungkapkan bahwa pendidikan yang paling utama dan pertama sekali didapatkan anak adalah di rumah. Organisasi besar seperti Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus kepada pendidikan dalam keluarga. Bahkan Negara Indonesia melalui undang-undang sistem pendidikan nasional menerangkan bahwa sekolah hanya tempat penitipan mandat dari seorang orang tua kepada guru di sekolah supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan benar. Lantas ketika pemerintah ini membuat kebijakan pembelajaran dari rumah maka hendaknya saling mendukung dan bekerjasama untuk mewujudkan anak-anak menjadi cerdas berkat didikan orang tua di rumah dan bimbingan guru di sekolah melalui online.
Rujukan
[1] Sutrisno . Suyatno, Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern. Yogyakarta: Kencana, 2015.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 165
[2] M. Sudin, Karakter Pendidik Muhammadiyah Meneguhkan Idealisme dan Pembentukannya. Yogyakarta: Tangan Emas, 2019.
[3] E. M. Onyema, S. Sen, and A. O. Alsayed, “Impact of Coronavirus Pandemic on Education,” J. Educ. Pract., no. June, 2020, doi: 10.7176/jep/11-13-12.
[4] M. P. dan K. Surat Edaran No 4 Tahun 2020, PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 1 9). Indonesia, 2020, p. 300.
[5] A. juli R. Butar-Butar, Kepustakaan Medis Pandemik di Dunia Islam. Medan: UMSUpress, 2020.
[6] H. Fore, “Jangan biarkan anak-anak menjadi korban tersembunyi pandemi COVID-19. Diambil kembali dari,” unicef.org, 2020. .
[7] Kemendikbud, “JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP PROPINS,” 2020. http://statistik.data.kemdikbud.go.id/.
[8] Subarto, “Momentum Keluarga Mengembangkan Kemampuan Belajar Peserta Didik Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19,” Adalah Bul. Huk. dan Keadilan, vol. 4, pp. 13–18, 2020.
[9] Kemendikbud, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahyn Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2020 di Masa Pandemi Covid-19. Indonesia, 2020.
[10] S. J. Daniel, “Education and the COVID-19 pandemic,” Prospects, no. 123456789, 2020, doi: 10.1007/s11125-020-09464-3.
[11] K. A. RI, “Alquran Terjemahnya,” 1998. [12] A. Majid Khon, Hadis Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan. Jakarta:
Kencana, 2012. [13] H. Reza Alavi, “Islamic Values : a Distincitive Framework for
Moral Education,” J. Moral Educ., vol. 36, 2007. [14] S. Idi Abdullh, Etika pendidikan pendidikan keluarga, sekolah dan
masyarakat. Jakarta: RajawaliPres, 2015. [15] Z. J. S. B. S. Mammud, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994. [16] Pimpinan Pusat ’Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah.
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015. [17] S. Soemarjan, Sosiologi Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gajah Mada
Press, 1990. [18] K. H. Dewantara, Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Taman Siswa, 1961. [19] Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005.
166 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[20] M. I. Abdullah, Pendidikan Keluarga Bagi Anak. Cirebon: Lektur,
2003. [21] H. Langgulung, Manusia dan Pendidikan,. Jakarta: Pustaka al-
Husna, 1990. [22] M. S. Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab
Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” Nadwa, vol. 8, 2014. [23] Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44, “Pedoman Hidup
Islami Warga Muhammadiyah,” Pimpinan Pusat Muhamamdiyah. Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, pp. 1–25, 2000.
[24] A. Reimers, Fernando M & Schleicher, “A framework to Guide an Education Response to the COVID-19 Pandemic of 2020,” Amerika Serikat, 2020.
[25] R. Oktaria and P. Putra, “Child Education in the Family As an Early Childhood,” J. Ilm. PESONA PAUD, vol. 7, no. 1, pp. 41–51, 2020.
[26] E. M. Onyema, F. A. O. Nwafor Chika Eucheria, and A. O. A. Shuvro Sen, Fyneface Grace Atonye, Aabha Sharma, “Impact of the 2019 – 20 Coronavirus Pandemic on Education,” Int. J. Heal. Prefer. Res., vol. 5, no. 20, pp. 31–44, 2020, doi: DOI: 10.13140/RG.2.2.27946.98245.
[27] U. S. P. Nasional, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, vol. 71. Indonesia, 2003, pp. 6–6.
[28] H. Supriyono. Iskandar and Sucahyono, PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASA KINI. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 167
Bab 12
Pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning Solusi dan Aksi Pembelajaran di Era New Normal Pandemi Covid 19 Nurul Zuriah 13
Pengantar
Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda Dunia saat ini telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik, telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi, social and physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini mengharuskan warganya untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah dan belajar di rumah.[1] Keadaan di luar prediksi normal berupa P a n d e m i covid-19 yang terjadi saat ini telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor kehidupan. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Data yang di up date setiap hari di seluruh dunia menggambarkan bertambahnya cakupan dan dampak covid-19. Negara Indonesia juga termasuk dalam keadaan darurat nasional. Angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat sejak diumumkan pertama kali ada masyarakat yang positif terkena virus covid-19 pada awal Maret 2020. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan di seluruh sektor kehidupan untuk diterapkan keadaan darurat dan deskresi.[2]
Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan dilakukan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelengaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.[3] Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat
13 Dr. Nurul Zuriah, Dosen Pendidikan Civic Hukum Univesitas Muhammadiyah Malang
168 | New Normal, Kajian Multidisiplin
segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekaranti-naan kesehatan, yang salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).[3]
Angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat sejak diumumkan pertama kali ada masyarakat yang positif terkena virus covid-19 pada awal Maret 2020. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan di seluruh sektor kehidupan untuk diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas atau suatu gedung, dalam hal ini kampus, menjadi cukup di rumah saja. Anjuran pemerintah untuk stay at home dan physical and social distancing harus diikuti dengan perubahan modus belajar tatap muka menjadi online atau berbasis daring.[2]
Pasca terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, sebagai awal dimulainya masa new normal (kenormalan baru). Sejumlah Kementerian/Lembaga negara telah menindakalnjutinya dengan sejumlah peraturan yang diberlakukan untuk wilayah dan lingkungan pekerjaannya, termasuk untuk aktivitas perekonomian, keagamaan dan Aparatus Sipil Negara. Sementara untuk dunia pendidikan seperti yang diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menetapkan Tahun Akademik 2020/2021 di perguruan tinggi tetap dimulai pada Agustus 2020. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi ini tetap dilaksanakan secara daring.
Salah satu metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk saat ini adalah metode Blended Learning. Blended Learning adalah pola pembelajaran campuran antara pembelajaran di kelas (face to face) dan online (webinar, LMS). Namun untuk saat pandemi ini yang digunakan adalah metode online dengan memanfaatkan multimedia baik sinkron (synchronous) dan asinkron (asynchronous).
Hal ini sejalan dengan semangat untuk mengubah paradigma pembelajaran dari teacher centered ke student centered, dengan meng-gunakan blended learning. Beberapa alasan yang mendukung adalah pertama; Blended Learning, merupakan pendekatan pembelajaran yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 169
mengintegritaskan pembelajaran tradisional tatap muka dan pem-belajaran jarak jauh yang menggunakan sumber maya dan belajar online dengan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. [4]. Untuk hal itu, Rooney [5], menegaskan bahwa metode blended learning, merupakan satu pendekatan yang menkoordi-nasikan antara pertemuan tatap muka dengan pembelajaran pem-belajaran secara daring. Hal itu juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk menggabungkan keunggulan dari dua jenis metode yang diguna-kan. Blended learning bermanfaat bagi peserta didik bisa lebih kepada penguasaan konsep pembelajaran dengan baik.[6]
Pembelajaran blendedlearning mengkombinasikan atau campuran antara pembelajaran face to face dengan bantuan Information And Communication Technology (ICT) dengan beberapa kelebihan sebagai berikut: (1) siswa berinteraksi langsung dengan isi pembelajaran; (2) dapat berinteraksi dengan teman; (3) berdiskusi kelompok dan bertukar pendapat; (4) mengakses E-library; (5) kelas virtual; (6) penilaian online: E-tuitions; (7) mengakses dan memelihara blog pembelajaran; (8) seminar on line (webinar); (9) melihat dosen ahli di youtube; (10) belajar online; melalui video dan audio; serta laboratorium virtual. Pembelajaran blended learning mengkombinasikan berbagai bentuk alat pembelajaran, misal-nya: kombinasi real time perangkat lunak, program pembelajaran ber-basis Web Onlie dan aplikasi lainnya yang mendukung kepada lingkungan belajar dan pengetahuan manajemen sistem. Pembelajar-an blended learning merupakan perpaduan antara online, tatap muka dan mandiri yang dipandu oleh mentor, guru atau dosen dengan pem-belajaran yang terstruktur.[3]
Kajian terdahulu mengenai pembelajaran daring dan blended learning ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan data terbaru, (1) W Darmalaksana, et all (2020) tentang analsis pembelajaran online masa WFH Pandemik Covid-19 sebagai tantangan pemimpin digital abad 21; [7] (2) Sanjaya (2020) mengkaji tentang 21 refleksi pembelajaran daring di masa darurat Covid-19. [8] (3) Yanti, et all, (2020) mengkaji tentang pemanfaatan portal rumah belajar kemendikbud sebagai media pembelajaran daring di Sekolah Dasar. [9] Berdasarkan laporan tersebut, kajian mengenai pembelajaran PPKn berbasis blended learning sebagai solusi dan aksi pembelajaran di era New Normal dan Pandemi Covid 19 belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tentang Pembelajaran PPKn berbasis blended learning sebagai sebuah solusi dan aksi pembelajaran di era New Normal Pandemi Covid 19 perlu
170 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dilakukan. Sehingga diharapkan respon yang diperoleh dapat meng-gambarkan proses pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis blended learning di Era New Normal dan pandemi Covid-19 saat ini dan dijadikan informasi dasar bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan pembelajaran blended learning dan daring di masa mendatang.
Pembahasan
Blended Learning berasal dari kata Blended dan Learning. Blended membawa maksud campuran dan Learning bermaksud belajar. Dari kedua unsur kata tersebut dapat diketahui bahwa konsep Blended Learning ini merupakan percampuran pola belajar. Menurut Mosa, Yoo, dan Sheets[10], pola belajar yang dicampurkan adalah dua unsur utama yaitu pembelajaran di kelas dengan online learning. Konsep blended learning ialah percampuran model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitor dan teman yang membuat situasi yang kon-dusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik [11]
Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukan komputer, walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi (blended). Terjadinya pembelajaran, awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pelajar, setelah ditemukan mesin cetak maka guru memanfaatkan media cetak. Pada saat ditemukan media audio visual, sumber belajar dalam pembelajaran mengombinasi antara pengajar, media cetak, dan audio visual. Namun blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajar secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan mengga-bungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, teknologi audio, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan teknologi m-learning (mobile learning). Dalam blended learning terdapat enam unsur yang harus ada, yaitu: (1) tatap muka (2) belajar mandiri, (3) aplikasi, (4) tutorial, (5) kerjasama, dan (6) evaluasi.[11]
Ada empat karakteristik konsep pembelajaran blended learning, yang merupakan kelebihannya, yaitu: Pertama, menggabungkan mode teknologi yang berbasis web misalnya kelas virtual langsung, pem-belajaran kolaboratif, streaming video, audio dan teks. Kedua, meng-gabungkan pendekatan pedagogis misalnya kognitivisme, konstruktivis-me, behaviorisme untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal
New Normal, Kajian Multidisiplin | 171
dengan atau tanpa penggunaan teknologi. Ketiga, menggabungkan segala bentuk teknologi pembelajaran misalnya video tape, CD ROM, pelatihan berbasis web, film dengan dipimpin struktur tatap muka. Keempat, mencampur teknologi pembelajaran yang sebenarnya untuk menciptakan efek pembelajaran dan kerja yang harmonis. Beberapa alasan yang mendorong penggunaan blended learning antara lain: keka-yaan pedagogis, akses ke pengetahuan, interaksi sosial, agensi pribadi, efektifitas biaya dan kemudahan revisi.[3][12]
Perguruan tinggi seharusnya cenderung lebih mudah beradaptasi dengan blended learning, karena mahasiswa sudah menggunakan pola belajar mandiri, beda dengan siswa sekolah. Dalam pelaksanaanya blended learning rekan-rekan perlu meramu blended learning di masing-masing institusi pendidikan, karena implementasi blended learning pasti berbeda-beda karena harus student-oriented, sesuai kebutuhan. Fokusnya adalah penyediaan materi dan panduan yang jelas. Posisi multimedia dalam blended learning bukan tujuan, tapi cara mencapai tujuan. Untuk memudahkan pembelajaran yang dirasa sulit ketika disampaikan secara langsung.
Ada beberapa manfaat multimedia dalam blended learning, yaitu : a. Animasi mempermudah pemahaman mahasiswa, b. Simulasi meningkatkan kreativitas mahasiswa, c. VR/AR/MR meningkatkan partisipasi belajar mahasiswa, d. AI-Based multimedia mempercepat penguasaan mahasiswa e. Multimedia Gamifikasi membuat mahasiswa ketagihan belajar, f. Proses Evaluasi (Tes/Ujian) berjalan efektif dan menyenangkan dengan berbagai metode seperti: Gamifikasi, social media, AR/VR/MRMR, IOT Big Data, Expert System, Machine Learning. Adanya pandemi Covid-19 ini memaksa kita melangkah lebih cepat dalam hal inovasi pembelajaran.
Di samping itu ada beberapa kelebihan dan kelemahan model blended learning. Kelebihannya adalah: (1) Hemat waktu, (2) Hemat biaya, (3) Pembelajaran lebih efektif dan efisien, (4) Peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran, (5) Peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri, (6) Memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online, (7) Peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka, (8) Pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar, (9) Menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet, (10) Memperluas jangkauan pembelajaran/pelatihan, (11) Hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran, dan lain sebaginya. Adapun
172 | New Normal, Kajian Multidisiplin
kekurangannya: (1) Sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, (2) Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta, (3) Akses internet yang tidak merata di setiap tempat, dan sebagainya.[11]
Implementasi blended learning tentunya tidak terlepas dari kom-ponen-komponen utama yang bersinergi , sehingga dapat menghasilkan luaran pembelajaran yang diharapkan. Dengan kata lain, penerapan blended learning tidak hanya berhubungan dengan penggunaan aplikasi tertentu. Namun, penerapan blended learning adalah sikulus yang meliputi perencanaan (planning), pelaksanaan (doing), evaluasi (evaluating), dan perencanaan ulang (replanning). Pada proses perencanaan, selain ada perencanaan dari level institusi, tentunya perencanaan juga dilakukan oleh dosen/guru. Pada level institusi perencanaan bisanya meliputi aspek kebijakkan dan peraturan akademik, pendanaan, ketersediaan insfrastruktur, dan ketersediaan sumber daya manusia. Sementara itu dosen/guru juga harus mempersiapkan peren-canaan, khususnya dalam desain pembelajaran dan media pem-belajaran.[13]
Implementasi Pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning
Penerapan pembelajaran PPKn berbasis blended learning di tengah Pandemi Covid-19 pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada yang merasa senang dan tidak senang.
a. Perasaan Senang Mahasiswa Diterapkannya Pembelajaran berbasis Blended Learning
Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa yang merasa senang atas penerapan pembelajaran blended learning mempunyai alasan yaitu pembelajaran dapat dilakukan di rumah sehingga mahasiswa dapat berkumpul dengan keluarganya. Ditambah dengan belajar dari rumah mahasiswa dapat belajar lebih banyak hal tentang kehidupan bermasya-rakat, perekonomian, serta pertanian yaitu dengan mempraktikkan secara langsung ilmu yang didapatkan selama kuliah.
Mahasiswa dalam proses pembelajaran blended learning juga merasa nyaman karena dapat belajar dari rumah dan proses pem-belajaran jadi lebih rileks, di tengah pembelajaran mahasiswa dapat beristirahat secara cukup. Mahasiswa dapat menghemat tenaga dan menghemat waktu. Mahasiswa akan lebih selektif dalam menyusun manajemen waktunya, baik untuk mempelajari materi yang diberikan, mengerjakan tugas, dan mempraktikkan ilmu yang telah di dapatkan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 173
Di tengah Pandemi mahasiswa tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung atau luring. Interaksi dalam belajar antara dosen dengan mahasiswa tidak berlangsung secara efektif namun dengan model pembelajaran daring/blended learning mahasiswa merasa terbantu dalam belajarnya. Mahasiswa berpendapat bahwa pembelajaran blended learning lebih baik tetap dilaksanakan agar mereka tidak ketinggalan materi kuliah. Mahasiswa menyebutkan bahwa pembelajaran online atau daring/blended learning merupakan solusi yang cukup efektif dan fleksibel untuk diterapkan di era new normal di tengah pandemi seperti ini.
Mahasiswa secara cepat beradaptasi dalam aktivitas belajarnya dengan diterapkannya pembelajaran secara daring/blended learning. Ber-dasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat beradaptasi dengan cepat dengan memanfaatkan teknologi yang memang menjadi tuntutan di era 4.0 ini. Mahasiswa banyak menggu-nakan fitur-fitur aplikasi yang menarik yang dapat mendukung proses belajar serta penyelesaian tugas mereka. Mahasiswa cukup antusias dengan pembelajaran secara online, karena menurut salah satu maha-siswa dengan pembelajaran secara online dapat mempersiapkan kami untuk bersaing di era digital. Dalam pembelajaran secara blended learning mahasiswa banyak diberikan tugas untuk membuat vlog atau video pembelajaran, bentuk penugasan seperti ini mahasiswa merasa senang karena akan lebih menguasai teknologi.
Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran secara blended learning di tengah pandemi Covid-19 dapat membuat mahasiswa merasa senang karena dilatarbelakangi berbagai alasan. Alasan yang pertama, karena mereka dapat dekat dengan keluarga dan dapat belajar secara langsung tentang kehidupan bermasyarakat. Kedua, mahasiswa akan lebih selektif dalam menyusun manajemen waktu. Ketiga, mahasiswa semakin menguasai teknologi.
b. Perasaan Tidak Senang Mahasiswa Diterapkannya Pembelajaran berbasis Blended Learning
Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pembelajaran harus berlangsung secara blended learning sehingga mahasiswa harus mengikuti instruksi ini untuk belajar dari rumah. Dengan kondisi saat ini mahasiswa juga ada yang merasa tidak senang dengan pembelajaran yang dilakukan secara blended learning.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran secara blended learning membuat mahasiswa sulit menerima atau memahami materi karena tidak adanya praktik pembelajaran secara
174 | New Normal, Kajian Multidisiplin
langsung. Bagi mahasiswa, tidak semua materi dapat dipahami dengan membaca apalagi dalam mata kuliah kewarganegaraan yang seharusnya dapat dilakukan dengan banyak diskusi. Pembelajaran berlangsung kurang intensif karena hanya dilakukan secara blended learning, maha-siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung seperti dapat berbicara atau menyampaikan pendapat di depan dosen dan mahasiswa lainnya. Salah satu mahasiswa menyebutkan bahwa:
“Selama melakukan daring/ blended learning kita hanya mendapatkan teori tanpa praktik padahal output yang harus didapatkan dari kuliah adalah mampu terjun ke masyarakat, lantas bagaimana kami mampu turun ke masyarakat jika hanya mendapat teori saja karena kita semua mengetahui bahwa teori belum tentu benar di lapangan”.
Mahasiswa merasa dengan pembelajaran yang berlangsung secara blended learning membuat tugas semakin banyak sehingga mengakibatkan rasa malas dalam belajar karena merasa jenuh. Apalagi ketika tugas yang diberikan bersamaan batas akhir pengumpulannya dengan mata kuliah lain. Salah satu mahasiswa berpendapat bahwa “dengan pembelajaran secara online atau daring atau blended learning terkadang mahasiswa hanya mendapat penugasan tanpa adanya penjelasan terkait materi dari Dosen sehingga dalam menjawab tugas terpaksa mencari jawaban lewat media internet seperti google”.
Penerapan pembelajaran secara blended learning membuat sistem belajar mahasiswa kurang berjalan secara efektif. Sistem belajar-mengajar berlangsung tidak teratur terkadang mengakibatkan mahasiswa lupa jam kuliah online sehingga mahasiswa melewatkan pembelajaran daring. Dalam sudut pandang yang lain, pembelajaran secara blended learning yang berlangsung secara tidak sistematis cukup menguras banyak kuota internet untuk kebutuhan mendownload materi, melakukan pem-belajaran online, dan mencari tugas sehingga semakin menambah pengeluaran mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa juga berasal dari pedalaman dan pegunungan atau tempat tinggal mereka berada jauh dari tower provider sehingga mengalami kondisi susah jaringan atau sinyal. Tidak terkadang mahasiswa yang berasal dari daerah harus berjalan jauh untuk mendapatkan koneksi jaringan yang bagus.
Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada perasaan tidak senang dari mahasiswa dengan diterapkannya pem-belajaran blended learning di tengah Pandemi Covid-19 ini. Pertama, karena kesulitan menerima atau memahami materi karena tidak adanya praktik pembelajaran secara langsung. Kedua, tugas mahasiswa semakin banyak
New Normal, Kajian Multidisiplin | 175
sehingga mengakibatkan mereka semakin malas dalam belajar karena merasa jenuh. Ketiga, adanya sistem belajar mengajar secara online yang tidak tersistematis sehingga mengakibatkan pengeluaran mahasiswa semakin besar untuk membeli kuota internet. Ditambah ada beberapa mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah pedalaman dan pegunung-an yang mengalami kondisi susah jaringan atau sinyal.
Dilihat dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas jika seluruhnya atau minimal 75% siswa terlibat aktif dan menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri yang tinggi dan dari segi hasil proses pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa seluruhnya atau minimal 75% sesuai dengan kompetensi dasar.[14][15][16] Pada penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran berbasis blended learning dikatakan berhasil ketika minimal 75% dari jumlah keseluruhan siswa telah memiliki Kemandirian dalam Belajar, Kemampuan Critical Thinking, dan memperoleh Prestasi Belajar minimal 75 untuk nilai angka, atau B+ untuk nilai huruf.
Berdasarkan pengimplementasian blended learning dalam pembelajaran didapatkan hasil-hasil sebagai berikut:
1. Aspek Kemandirian Belajar
Terdapat lima kriteria yang digunakan untuk mengukur aspek Kemandirian Belajar mahasiswa. Kriteria-kriteria tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman untuk menilai jumlah mahasiswa yang mempunyai Kemandirian Belajar antara sebelum penelitian, penelitian siklus 1, penelitian siklus 2, dan penelitian siklus 3. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut.
176 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Berdasarkan analisis data yang sudah disajikan di atas ditemukan bahwa Kemandirian Belajar sebelum penelitian adalah sebesar 14,3%, sedangkan setelah siklus 3 pengimplementasian Strategi Blended Learning adalah sebesar 85,7%. Apabila dijabarkan berdasar kritera-kriterianya dapat dijabarkan sebagai berikut: 85,7% mahasiswa mampu mengambil inisiatif untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya, 85,7% mahasiswa mampu memformulasikan tujuan belajarnya, 92,9% mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber belajarnya, 85,7% maha-siswa mampu untuk memilih dan mengimplementasikan strategi belajar yang cocok untuknya, serta 78,6% mahasiswa mampu mengevaluasi hasil belajarnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa untuk belajar mandiri antara sebelum pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning dan setelah pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning (siklus 1, siklus 2, dan siklus 3).
2. Aspek Critical Thinking
Terdapat 13 kriteria yang digunakan untuk mengukur aspek Critical Thinking mahasiswa. Kriteria-kriteria tersebut kemudian diguna-kan sebagai pedoman untuk menilai jumlah mahasiswa yang mempunyai kemampuan Berpikir Kritis antara sebelum penelitian, penelitian siklus 1, penelitian siklus 2, dan penelitian siklus 3. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut.
0
2
4
6
8
10
12
14
Pra PTK Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3
Tabel 1: Kemandirian Belajar Mahasiswa
Inisiatif Formulasi Identifikasi Pilihan Evaluasi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 177
Tabel 2 Berpikir Kritis
Berdasarkan analisis data yang sudah disajikan di atas ditemu-kan bahwa tingkat Critical Thinking mahasiswa sebelum penelitian adalah sebesar 19,3%, sedangkan setelah siklus 3 pelaksanaan pem-belajaran berbasis blended learning adalah sebesar 88,6%. Apabila dijabarkan berdasar kritera-kriterianya dapat dijabarkan sebagai berikut: 92,9% mahasiswa berpikiran terbuka, 85,7% mampu meng-ambil sikap ketika bukti dan alasan sudah cukup, 85,7% mampu mempertimbangkan keseluruhan situasi, 85,7% mampu membekali dengan informasi, 92,9% mahasiswa mampu mencari kebenaran sebanyak-banyaknya, 85,7% mahasiswa mampu menyelesaikan ma-salah dengan sistematis dan menyeluruh, 92,9% mahasiswa mampu mencari alternatif-alternatif, 92,9% mahasiswa mampu mencari alasan, 85,7% mampu mengingat-ingat hal yang mendasar, 85,7% mahasiswa mampu mempergunakan sumber yang kredibel dan menyebutkannya, serta 92,9% sensitif terhadap perasaan, tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuan orang lain. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis antara sebelum pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning dan setelah pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning (siklus 1, siklus 2, dan siklus 3).
3. Aspek Prestasi Belajar
Pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning, mahasiswa diberi penilaian untuk penugasan, partisipasi di kelas dan
178 | New Normal, Kajian Multidisiplin
diskusi kelompok, serta nilai UAS. Kemudian dibuat pengelompokan mahasiswa dalam 3 kelompok untuk memudahkan pengelompokan mahasiswa berdasarkan ketuntasannya. Standar ketuntasan ditetapkan sebesar 75. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 3 berikut.
Berdasarkan analisis data yang sudah disajikan di atas dapat
dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis blended learning tidak hanya dapat meningkatkan Kemandirian Belajar dan kemampuan Critical Thinking mahasiswa, akan tetapi juga dapat me-ningkatkan Prestasi Belajar mahasiswa. Dalam siklus 1, persentase jumlah mahasiswa yang mempunyai rata-rata nilai tugas dan partisipasi siswa lebih besar sama dengan 75 adalah sebesar 57,1 %. Keadaan ini meningkat kembali pada implementasi siklus 2 menjadi 85,7% dan siklus 3 menjadi 92,9%. Peningkatan yang signifikan baru terlihat pada siklus ke-3dikarenakan mahasiswa masih belum familiar dengan strategi pembelajaran Blended Learning ini. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan strategi pembelajaran yang baru.
Berdasarkan capaian nilai UAS, terdapat 11 orang (78,6%) maha-siswa yang mendapatkan skor lebih besar sama dengan 75 dari total mahasiswa sebanyak 14 orang. Dari 3 orang yang belum tuntas tersebut, 1 orang tidak mengikut UAS, 1 orang mendapatkan skor 65 dan 1 orang mendapatkan skor 70. Di luar faktor penilaian aspek kognitif tersebut, bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning cukup sukses dengan adanya dukungan teknologi dan koneksi internet yang memadai.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 179
Hambatan dan Solusi Pembelajaran Blended Learning
Pembelajaran berbasis blended learning dengan sistem daring yang dilaksanakan oleh prodi PPKn FKIP UMM yang menjadi objek penelitian ini tentunya menimbulkan beberapa permasalah yang menjadi hambatan. Gambar 1 di bawah ini menunjukan beberapa hambatan yang dialami oleh responden selama proses pembelajaran berbasis blended learning dengan sistem daring ini.
Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat diketahui beberapa hambatan dalam pembelajaran sistem daring, mulai dari terbatasnya kuota, banyaknya tugas, penguasaan IT yang masih terbatas, jaringan ang tidak stabil, telat ‘masuk’ kuliah karena tidak terbiasa menggunakan daring, jaringan yang tidak stabil karena kondisi responden yang ada di pedesaan, dan lain sebagainya.
Gambar 1 Hambatan Proses Pembelajaran Berbasis Blended Learning
Dari sekian banyak kendala yang dialami oleh responden,
terdapat tiga jenis hambatan yang paling banyak dialami responden selama perkuliahan daring berbasis Blended Learning, yakni kuota yang terbatas sebanyak 21,5%, jaringan tidak stabil sebanyak 23,4% dan tugas yang menumpuk sebanyak 30,6%. Tentunya ketiga faktor tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk oleh responden itu sendiri dan istitusi. Seperti halnya kuota yang terbatas, ini harus diantisipasi oleh responden maupun istitusi. Institusi dapat menerap-kan beberapa langkah strategis seperti halnya menyiapkan dan menyediakan aplikasi e-learning yang rendah kuota (tidak memerlukan kuota internet besar) dalam mengaksesnya. Selain itu, terdapat
180 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pelayanan berupa kuota gratis puluhan giga bite (GB) dengan cara kerjasama dengan provider untuk mengakses layanan pendidikan. Kendala yang dihadapi mahasiswa ini adalah berkaitan dengan kuota internet. Dengan tidak sistematis pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen mengakibatkan penggunaan kuota semakin lebih besar. Akibatnya kebutuhan kuota semakin meningkat. Semakin mening-katnya kebutuhan kuota pengeluaran menjadi bertambah. Padahal dalam kondisi Pandemi seperti ini keuangan keluarga sedang menurun
Jaringan tidak stabil juga merupakan hambatan dalam proses pembelajaran dengan sistem daring. Keberadaan fasilitas jaringan merupakan hal yang utama dalam pembelajaran sistem daring, karena berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran. Keberadaan responden yang jauh dari pusat kota ataupun jauh dari jangkauan jaringan provider tentunya tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar. Kendala kedua, yaitu faktor jaringan atau sinyal. Banyak mahasiswa menyebutkan bahwa dalam pembelajaran secara daring koneksi jaringan atau sinyal sering menjadi faktor utama yang mempengaruhi. Terlebih ketika cuaca tidak mendukung seperti hujan, koneksi jaringan atau sinyal semakin terganggu. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses pembelajaran online/daring/blended learning yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa PPKn ada yang berasal dari daerah pedalaman dan pegunungan, sehingga dalam pembelajaran secara daring cukup sulit mendapatkan sinyal.
Kendala lain yang dihadapi mahasiswa adalah pada platform pembelajaran yang belum dikuasai. Platform yang digunakan dalam pembelajaran online/daring berbasis blended learning adalah: google classroom, LMS Moodle, dan WhatsApp. Adapun platform Youtobe dan Gmail sebagai media pendukung. Penggunaan platform moodle dan canvas yang disarankan oleh kampus sering memiliki kendala bagi mahasiswa karena mahasiswa belum terlalu familiar dengan media ini. Penggunaan platform moodle dalam pembelajaran online/daring juga membutuhkan sinyal yang kuat sehingga hal ini menjadi kendala oleh beberapa mahasiswa. Terkadang ketika mahasiswa mengerjakan tugas melalui platform moodle dan sinyal jaringan sedang tidak stabil maka pengerjaan tugas harus diulang. Selain itu dosen juga menggunakan platform google classroom untuk melangsungkan pembelajaran secara daring. Meskipun banyak mahasiswa yang sudah familiar dengan media ini, namun masih ada beberapa mahasiswa yang masih bingung menggunakan media ini.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 181
Kendala keempat yang dihadapi mahasiswa yaitu dalam penguasaan materi. Adanya pembelajaran secara daring menyebabkan interaksi antara Dosen dengan mahasiswa berkurang. Dosen yang menyampaikan materi melalui berbagai platform online, seperti LMS Moodle, Google Classroom, You Tube, WhatsApp terkadang tidak diberikan feedback ulasan bersama mahasiswa sehingga mahasiswa susah untuk memahami materi dan tidak jarang mahasiswa salah menafsirkan materi yang disampaikan Dosen. Terkadang dosen juga hanya memberikan tugas saja. Hal ini yang menyebabkan kendala bagi mahasiswa dalam penguasaan materi, selain karena mahasiswa terbiasa menerima materi dari Dosen secara langsung atau face to face.
Sementara yang menjadi hambatan terbesar berdasarkan gambar di atas, yang dirasakan oleh responden adalah adanya tugas yang menumpuk. Komponen ini dirasa menjadi hambatan bagi responden, karena kondisi pembelajaran dengan sistem daring yang masih belum bisa menyesuikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini akan perlahan membaik jika pembelajaran sistem daring ini sudah terbiasa dilaksanakan dalam proses perkuliahan. Selain itu, komunikasi yang “mencair” yang dibangun antara dosen dengan mahasiswa penting dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut.
Tiga hal besar yang menjadi hambatan bagi responden dalam pembelajaran dengan sistem daring ini tentunya memberikan efek psikologis bagi responden (Lihat Gambar 2).
Gambar 2 Pengaruh Hambatan Terhadap Kondisi Psikis
Mahasiswa Sebanyak 24% responden menyatakan bahwa hambatan tersebut
sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis responden. Hanya sebagian kecil saja yang menyatakan bahwa hambatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi psikisnya. Hal ini tentunya harus
182 | New Normal, Kajian Multidisiplin
diantisipasi oleh responden mengingat kesehatan mental menjadi hal yang utama dipertahankan.
Responden yang menyatakan bahwa hambatan tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikis memiliki aktivitas lain untuk mengantisipasinya. Sebanyak 72% memiliki aktivitas lain untuk mengantisipasi akan pengaruh terhadap kondisi psikis. Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh responden yaitu seperti menonton, berolahraga, bercengkrama dengan keluarga, komunikasi dengan teman sejawat dan beberapa penghargaan lainnya yang dilakukan atas prestasi diri yang diraih. Jika responden dapat mengantisipasi kondisi gangguan tersebut, maka dapat mempertahankan kondisi normal dan meningkatkan minat belajar mahasiswa sehingga hasil belajarnya pun meningkat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Nurhasanah dan Sobandi [1][17] yang menyatakan bahwa minat belajar ini merupakan determinasi dari hasil belajar siswa sehingga minat belajar ini harus tetap dipertahankan. Namun ketika hambatan yang ditemukan oleh mahasiswa dapat menimbulkan kesulitan belajar, maka salah satu solusinya adalah dilakukan melalui pendekatan psikologi kognitif [1][18]
Upaya Mengatasi Kendala Pembelajaran Berbasis Blended Learning
Pembelajaran online/daring berbasis Blended Learning yang diterapkan oleh Prodi PPKn FKIP UMM memiliki beberapa beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, seperti faktor jaringan atau sinyal, kuota internet, platform pembelajaran, dan penguasaan materi. Dalam mengatasi kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat dengan cepat beradaptasi untuk mengatasi kendala tersebut.
Pertama, dalam mengatasi masalah koneksi jaringan atau sinyal mahasiswa berusaha memposisikan diri dimana ada sinyal jaringan yang bagus untuk melaksanakan pembelajaran daring. Sorang mahasiswa untuk mencari sinyal jaringan yang stabil sampai harus pergi ke tepi sungai dan sawah. Apabila cuaca sedang buruk atau koneksi jaringan tidak stabil usaha yang dilakukan mahasiswa yaitu mencari hotspot wifi ke saudara yang memiliki koneksi yang bagus. Usaha lain yang dilakukan oleh mahasiswa agar memperoleh koneksi jaringan yang stabil yaitu pergi ke warung di desa yang memiliki wifi. Terkadang tidak jarang ada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas karena kendala jaringan sehingga harus mengkonfirmaskani ke Dosen pengampunya.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 183
Kedua, dalam mengatasi kendala kuota internet mahasiswa berusaha untuk menggunakan kuota internet seperlunya. Mahasiswa dalam mengatasi masalah ini sampai harus mengganti kartu provider yang jaringannya lebih bagus untuk digunakan di tempat mereka. Tidak jarang mahasiswa harus mengambil uang tabungannya untuk membeli kuota internet karena mahasiswa merasa tidak enak untuk meminta kepada orang tua karena kondisi ekonomi keluarga sedang tidak stabil.
Ketiga, dalam mengatasi penguasaan platform pembelajaran yang masih kurang oleh mahasiswa, mahasiswa sering melakukan sharing antar mahasiswa dalam penggunaan media yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring. Apabila masih bingung, mahasiswa akan menghubungi Dosen. Adapun upaya mahasiswa dalam mengatasi kendala platform pembelajaran secara spesifik ditunjukkan pada penjelasan berikut.
a. Google classroom
Mahasiswa dalam mengatasi kendala penggunaan platform google classroom yang diterapkan dalam pembelajaran online/daring yaitu dengan mengulik lebih dalam, mempelajari dan memahami apa saja fitur dalam google classroom melalui searching di internet. Mahasiswa jika masih mengalami kendala akan mengomunikasikan kepada dosen yang bersangkutan atau bertanya kepada mahasiswa lain bagaimana cara penggunaannya karena mahasiswa baru pertama kali menggunakan media google classroom ini. Jika sistem google classroom tidak bekerja dengan baik, mahasiswa mengupgrade aplikasi untuk mempermudah saat mengakses, dan mencari sinyal jaringan yang bagus agar cepat saat menerima notifikasi informasi materi maupun tugas yang diberikan oleh Dosen. Alternatif lain yang dilakukan ketika mahasiswa mengalami kendala dalam mendownload materi/tugas maka mahasiswa meminta bantuan kepada mahasiswa lain untuk mengirimkan materi/tugas via whatsapp. Apabila terkendala dalam mengirimkan tugas menggunakan google classroom maka mahasiswa akan mengirimkan tugas melalui whatsapp atau e-mail.
b. LMS Moodle
Mahasiswa dalam mengatasi kendala penggunaan platform LMS Moodle yang diterapkan dalam pembelajaran online/daring/blended learning yaitu dengan mencari sinyal yang bagus agar dapat mengakses media ini karena media ini menurut mahasiswa
184 | New Normal, Kajian Multidisiplin
membutuhkan sinyal yang kuat. Seringkali ketika mahasiswa mengakses media ini mengalami loading-nya cukup lama. Jadi ketika menggunakan media ini mahasiswa harus teliti mengecek deadline dan mengirimkan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline waktu pengerjaan karena untuk menghindari gangguan (trouble). Dan karena baru pertama menggunakan platform ini mahasiswa seringkali mengalami kebingungan ditambah menurut mahasiswa platform ini sulit untuk dipahami. Mahasiswa dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan mengomunikasikan dengan Dosen yang bersangkutan dan bertanya kepada mahasiswa lain.
c. WhatsApp
Mahasiswa dalam mengatasi kendala penggunaan platform Whatsapp yang diterapkan dalam pembelajaran online/daring/blended learning yaitu dengan mencari sinyal yang bagus agar dapat akses pada media ini lancar. Menurut mahasiswa WhatsApp merupakan media yang cukup efektif untuk digunakan dalam pembelajaran daring karena dapat berdiskusi dengan memanfaatkan fitur chat dan share video materi. Media Whatsapp lebih mudah digunakan dibanding dengan aplikasi lain, karena sering digunakan dan lebih familiar. Namun, saat pembelajaran melalui whatsaap tentunya banyak file materi maupun tugas yang dishare dan hal itu akan menyebabkan kapasitas memori ponsel penuh, untuk mengatasi hal tersebut mahasiswa memindahkan file-file materi dan tugas tersebut ke laptop. Kendala lain yang dihadapi mahasiswa yaitu tertimbunnya materi dan tugas yang diberikan Dosen sehingga mahasiswa harus lebih cermat untuk mengecek group Whatsapp dan jeli dalam mencari materi atau tugas. Selain itu agar mahasiswa tidak ketinggalan pembelajaran daring melalui media Whatsaap, mahasiswa mengaktifkan notifikasi Whatsapp group kelas sehingga informasi yang masuk dapat direspon dengan cepat.
Keempat, dalam mengatasi masalah penguasaan materi, maha-siswa biasa bertanya kepada Dosen dan bertanya kepada mahasiswa yang lain dengan memanfaatkan group kelas untuk melakukan diskusi.
Penutup
Blended learning dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. dalam Blended Learning secara umum terdapat 6 model, yaitu: Face-toFace
New Normal, Kajian Multidisiplin | 185
Driver model, Rotation model, Flex model, Online Lap model, Self Blend model dan Online Driver model. Unsur-Unsur pembelajaran berbasis blended learning mengkombinasikan antara tatap muka dan e-learning yang memiliki 6 (enam) unsur, yaitu: (a) tatap muka (b) belajar mandiri, (c) aplikasi, (d) tutorial, (e) kerjasama, dan (f) evaluasi. Kelebihan model ini adalah: Hemat waktu, Hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien, dan sebagainya. Dalam hal ini strategi pendidik untuk meng-antisipasi tuntutan pembelajaran di masa yang akan datang mengguna-kan Blended Learning.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning dalam PPKn sebagai solusi dan aksi pembelajaran di era new normal dan pandemi covid 19, dapat meningkatkan Kemandirian Belajar dan kemampuan Critical Thinking mahasiswa, serta mampu mening-katkan Prestasi Belajar mahasiswa. Hambatan, solusi dan aksi dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem daring berbasis blended learning, menjadi bahasan yang menarik dalam masa pandemi Wabah Covid-19 ini. Di luar kesuksesan pelaksanaan pembelajaran PPKn berbasis Blended Learning di atas, perlu disadari bahwa strategi pembelajaran ini relatif baru di Indonesia, dan booming ketika masa pandemi covid 19. Pada Pelaksanaannya hendaknya dosen atau pengajar memperhatikan dukungan teknologi dan koneksi internet yang memadai sehingga dapat memperlancar implementasi strategi pembelajaran blended learning ini. Kesiapan teknologi dan koneksi internet yang memadai ini perlu dilihat baik dari sisi dosen maupun mahasiswanya. Tanpa adanya dukungan yang memadai, sebaiknya dosen lebih memilih penggunaan pembelajaran berbasis kelas (klasikal). Selain itu, dosen juga perlu mempertimbangkan faktor biaya. Guna menekan faktor biaya, para dosen dapat memanfaatkan tawaran aplikasi yang bebas biaya di internet sehingga tidak perlu membangun sistem informasi yang kompleks sendiri untuk pelaksanaan pembelajarannya.
Rujukan
[1] D. Jamaluddin, T. Ratnasih, H. Gunawan, and E. Paujiah, “Pembelajaran daring masa pandemik Covid-19 pada calon guru: hambatan, solusi dan proyeksi,” LP2M.
[2] D. R. A. U. Khasanah, H. Pramudibyanto, and B. Widuroyekti, “Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19,” J. Sinestesia, vol. 10, no. 1, pp. 41–48, 2020.
[3] E. Komara, “SISTEM BLENDED LEARNING PADA ERA
186 | New Normal, Kajian Multidisiplin
PANDEMI COVID 19,” no. 2004, 2006.
[4] A. Harding, D. Kaczynski, and L. Wood, “Evaluation of blended learning: analysis of qualitative data,” in Proceedings of The Australian Conference on Science and Mathematics Education (formerly UniServe Science Conference), 2012, vol. 11.
[5] A. A. Okaz, “Integrating blended learning in higher education,” Procedia-Social Behav. Sci., vol. 186, pp. 600–603, 2015.
[6] B. Means, Y. Toyama, R. Murphy, and M. Baki, “The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature,” Teach. Coll. Rec., vol. 115, no. 3, pp. 1–47, 2013.
[7] W. Darmalaksana, R. Hambali, A. Masrur, and M. Muhlas, “Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21,” Karya Tulis Ilm. Masa Work From Home Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pp. 1–12, 2020.
[8] R. Sanjaya, 21 Refleksi Pembelajaran Daring di Masa Darurat. SCU Knowledge Media, 2020.
[9] M. T. Yanti, E. Kuntarto, and A. R. Kurniawan, “Pemanfaatan Portal Rumah Belajar Kemendikbud sebagai Model Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar,” Adi Widya J. Pendidik. Dasar, vol. 5, no. 1, pp. 61–68, 2020.
[10] Z. Hussin, S. Siraj, G. Darusalam, and N. H. M. Salleh, “Kajian Model Blended Learning dalam Jurnal Terpilih: Satu Analisa Kandungan,” JuKu J. Kurikulum Pengajaran Asia Pasifik, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2017.
[11] A. K. Amin, “Kajian Konseptual Model Pembelajaran Blended Learning berbasis Web untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar,” J. Pendidik. Edutama, vol. 4, no. 2, pp. 51–64, 2017.
[12] A. Alammary, J. Sheard, and A. Carbone, “Blended learning in higher education: Three different design approaches,” Australas. J. Educ. Technol., vol. 30, no. 4, 2014.
[13] R. Sidiq, “OPINI BELER (OPTIMALISASI KOMPETENSI BLENDED LEARNING) UNTUK GURU DALAM MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG ERA REVOLUSI 4.0,” 2019.
[14] A. R. Sari, “Strategi blended learning untuk peningkatan kemandirian belajar dan kemampuan critical thinking mahasiswa di era digital,” J. Pendidik. Akunt. Indones., vol. 11, no. 2, 2013.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 187
[15] U. Masitoh, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Pembelajaran Dd/Ct Dengan Media Power Point Pada Materi Bumi Dan Benda Langit Siswa Kelas X Program Keahlian Tata Busana 2 SMKN N 4 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
[16] Y. D. Prasetyo, J. Ikhsan, and R. L. P. Sari, “The Development of Android-Based Mobile Learning Media as Chemistry Learning for Senior High School on Acid Base, Buffer, Solution, and Salt Hydrolysis,” J. Educ. Math. Sci., vol. 15, p. 18, 2014.
[17] S. Nurhasanah and A. Sobandi, “Minat belajar sebagai determinan hasil belajar siswa,” J. Pendidik. Manaj. Perkantoran, vol. 1, no. 1, pp. 128–135, 2016.
[18] R. Idris, “Mengatasi kesulitan belajar dengan pendekatan psikologi kognitif,” Lentera Pendidik. J. ilmu Tarb. dan Kegur., vol. 12, no. 2, pp. 152–172, 2017.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 189
Bab 13
Problematika Literasi Matematika yang dihadapi Guru dan Siswa pada Sekolah Berbasis Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Umi Farihah14, Dimas Danar Septiadi15, Arik Hariati16
Pengantar
Literasi matematika merupakan hal yang sangat penting karena literasi matematika menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberi alasan dan mengomunikasikan ide secara efektif pada pemecahan masalah matematis yang mereka temui [1]. Hal inilah yang menghubungkan matematika yang dipelajari di ruang kelas dengan berbagai macam situasi dunia nyata. Menurut OECD literasi matematika adalah kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Dalam hal ini termasuk penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelas-kan dan memprediksi suatu kejadian atau fenomena [2]. Dengan penguasaan literasi matematika, setiap individu akan dapat mereflek-sikan logika matematis untuk berperan pada kehidupannya, komu-nitasnya, serta masyarakatnya. Literasi matematika menjadikan individu mampu membuat keputusan berdasarkan pola pikir matematis yang konstruktif.
Namun kemampuan literasi matematika peserta didik di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya mutu SDM bangsa Indonesia saat ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan, khususnya matematika. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator. Di tingkat nasional, evaluasi pembelajar-an matematika di sekolah dilakukan menggunakan standar Ujian Nasional (UN). Sedangkan, di level internasional, saat ini terdapat dua asesmen utama yang menilai kemampuan matematika siswa, yaitu Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA). Dalam hal kemampuan matematika, survei hasil studi TIMSS, yang dilakukan setiap empat tahun yang dimulai tahun 1999, tahun 2011 menempatkan Indonesia pada 14 Dr. Umi Farihah, M.M., M.Pd, Dosen Tadris Matematika, IAIN Jember, Jember 15 Dimas Danar Septiadi, M.Pd, Dosen Tadris Matematika, IAIN Jember, Jember 16 Arik.Hariati, S.Pd, Guru Matematika, SMP Ainul Yaqin Ajung, Jember
190 | New Normal, Kajian Multidisiplin
posisi 36 dari 40 negara. Tahun 2015 hasilnya memperlihatkan bahwa peserta didik Indonesia belum menunjukkan prestasi memuaskan. Kemampuan Matematika peserta didik Indonesia, hanya mampu menempati peringkat 45 dari 50 negara, dengan pencapaian skor 397 dan masih di bawah skor rata-rata internasional yaitu 500 [3].
Rendahnya mutu pendidikan dapat pula dilihat dalam laporan studi PISA tahun 2015. Rangking Indonesia untuk Sains 62, Matematika 63, dan Membaca 64 dari 70 negara [4] . Pada PISA 2012 lalu, ranking Sains dan Matematika adalah 64 dari 65 sedangkan Membaca 61 dari 65 negara. Skor rata-rata untuk PISA 2015 (dan 2012) adalah skor Sains 403 (382), Matematika 386 (375) dan Membaca 397 (396). Fokus studi PISA adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam kehidup-an sehari-hari. Studi TIMSS dan PISA tersebut intinya terletak pada kekuatan penalaran matematis siswa serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kelemahan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika yang bersifat formal dengan permasalahan dalam dunia nyata [1]. Memperhatikan rendahnya kemampuan siswa Indonesia dalam survei tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah mengantisipasinya dengan melakukan beberapa perubahan kurikulum. Hingga dalam kondisi pandemi seperti sekarang pun pembelajaran masih harus tetap dilakukan yaitu dengan pembelajaran secara online.
Corona Virus Disease atau Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 suatu penyakit yang mewabah pada hampir seluruh negara di dunia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan tercatat 188 negara di dunia terjangkit Covid-19 [5]. Kejadian pandemi wabah Covid-19 tidak hanya menggemparkan lingkup nasional saja, namun ranah internasional disibukkan dengan kehadiran wabah virus covid-19, kejadian ini menghambat berbagai segala aktvitas kehidupan manusia dari berbagai sektor bidang, terutama dalam bidang pendidikan yaitu dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar baik sekolah-sekolah maupun tingkat perguruan tinggi. Demikian, di tahun 2020 ini kegiatan belajar mengajar akan berbeda dengan sebelumnya, siswa maupun tenaga kependidikan dituntut untuk beradaptasi dari keadaan sebelum kehadiran wabah covid-19.
World Health Organization merekomendasikan salah satu langkah pemutusan penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 191
pembatasan perjalanan, karantina, pembatasan jam malam, pengendalian bahaya di tempat kerja, dan penutupan fasilitas umum. Pandemi ini menyebabkan gangguan yang parah pada berbagai bidang sosial mapun ekonomi. Bidang pendidikan pun mengalami gangguan yang cukup signifikan. Sekolah dan universitas telah ditutup, baik secara nasional atau skala lokal di beberapa negara terjangkit COVID-19. Social distancing yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat berdampak pada kondisi pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah harus tetap terlaksana guna memenuhi kebutuhan siswa. Solusi yang ditawarkan saat ini dengan melakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online learning dari rumah masing-masing.
Wabah Covid-19 mendesak pengujian pendidikan jarak jauh yang hampir belum pernah dilakukan secara serempak sebelumnya bagi semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru hingga orang tua. Mengingat pada masa pandemi maka waktu, lokasi, dan jarak menjadi permasalahan besar saat ini [6] sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Ini memberikan tantangan kepada semua elemen dan jenjang pendidikan untuk mempertahankan agar kelas tetap aktif meskipun sekolah telah ditutup. Krisis kesehatan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 telah mempelopori pembelajaran online secara serempak. Tsunami pembelajaran online telah terjadi hampir di seluruh dunia selama pandemi Covid-19 [7]. Guru dan pendidik sebagai elemen penting dalam pembelajaran diharuskan melakukan migrasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendidikan tatap muka tradisional ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh [8]. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang tidak terbatas pada revolusi industri 4.0 saat ini. Pembelajaran online sangat efektif untuk melaksanakan pembelajaran meskipun pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda [9]. Hal ini mampu menyelesaikan permasalahan keterlambatan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Pandemi Covid-19 secara tiba-tiba mengharuskan elemen pendidikan untuk mempertahankan pembelajaran secara online. Kondisi saat ini mendesak untuk melakukan inovasi dan adaptasi terkait pemanfaatan teknologi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran [10]. Praktiknya mengharuskan pendidik maupun peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa
192 | New Normal, Kajian Multidisiplin
aplikasi, website, jejaring sosial, maupun learning management system (LMS) [11]. Banyak kendala dalam pembelajaran online diantaranya adalah penggunaan internet yang tinggi sehingga berpengaruh pada kesehatan peserta didik. Kendala lain yang ditemukan yakni kemampuan orang tua untuk memberikan fasilitas pendidikan online [12] seperti penggunaan jaringan internet yang membutuhkan biaya [13].
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia langsung merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Dengan isian antara lain kaitan dengan protokol dan prosedur kemanan saat sekolah kembali buka, seperti ringkasannya sebagai berikut: 1) Pengaturan mekanisme antar jemput siswa oleh satuan pendidikan. 2) Kebersihan dan strerilisasasi sarana-prasarana sekolah secara rutin minimal dua kali. 3) Pemantauan secara rutin kondisi kesehatan warga sekolah oleh pihak sekolah kaitang dengan gejala corona. 4) Penyediaan fasilititas pencucui tangan menggunakan sabun oleh pihak sekolah wajib diberikan. 5) Menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti menjaga jarak dan etika batuk dan bersih yang benar. 6) Pembuatan narahubung oleh sekolah berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di lingkungan sekolah.
Keputusan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut akan menjadi acuan dalam perubahan yang cukup besar bagi dunia pendidikan menuju new normal, baik itu dalam pengelolahan sekolah maupun peserta didik. Peraturan ini juga berlaku di lingkungan sekolah berbasis Islam di Kabupaten Jember. Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Problematika Literasi Matematika yang Dihadapi Guru dan Siswa pada Sekolah Berbasis Islam di Kabupaten Jember pada Masa Pandemi Covid-19”.
Pembahasan
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang masslah PISA sebagai bagian dari numerasi, pembelajaran berbasis numerasi, pembelajaran berbasis online di era new normal, dan problematika pembelajaran numerasi di era pandemic covid pada sekolah berbasis Islam di Kabupaten Jember.
Masalah PISA sebagai bagian dari numerasi
Berdasarkan hasil PISA untuk Indonesia tahun 2018, skor matematika dibawah rata-rata. Rata-rata skor PISA anggota OECD (The
New Normal, Kajian Multidisiplin | 193
Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk nilai matematika adalah 489 sedangkan nilai matematika Indonesia berada di kisaran nilai 375. Jika dilihat dari beberapa tes PISA yang telah diikuti Indonesia sejak 2000, kemampuan literasi matematika mengalami penurunan., skor Indonesia di awal mengikuti tes PISA mencapai angka 371 dan mengalami peningkatan sebesar 382 di tahun 2003. Pada tahun 2006 skor Indonesia mencapai angka 393 dan di tahun 2009 mencapai skor 402, kemudian terus mengalami penurunan 396 di tahun 2012, 397 di tahun 2015 (penurunan satu angka dari tahun sebelumnya), dan titik terendah di tahun 2018 yaitu di poin 371. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farihah et al. pada sekolah berbasis Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di sekolah berbasis Islam di Kabupaten Jember dengan mengambil 126 responden menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika tipe PISA [14] seperti yang terlihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Kesalahan Siswa Dari gambar terlihat bahwa kesalahan siswa menunjukkan siswa
belum bisa menyelsaikan soal tipe PISA. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu siswa di salah satu tipe kesalahan sebagai berikut .
Siswa
melakukan
kesalahan
memahami soal
hingga penulisan
jawaban akhir
194 | New Normal, Kajian Multidisiplin
P : Bagaimana cara dek fahmi menyelesaikan soal ini? S1 : Saya bingung bu, soalnya sulit . P : Oh iya-iya. Terus yang ada dilembar jawaban ini apa
maksudnya dek? S1 : Itu saya tulis dengan cara saya sendiri bu, tapi saya yakin itu
salah. Karena memang saya tidak tahu caranya yang penting saya isi bu. Maaf ya bu.
P : Tidak apa-apa dek. Memang perlu banyak latihan agar terbiasa mengerjakan soal seperti ini
S1 : Iya bu. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa siswa
masih merasa kebingungan dalam menyelesaikan soal. Dari keseluruhan data di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaiakan soal PISA masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa juga masih sangat rendah karena siswa belum terampil dalam mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Cockroft bahwa numerasi merupakan kemampuan atau keahlihan seseorang dalam menggunakan angka untuk menyelesai-kan dengan praktis berbagai masalah sehari hari [15]. Kemampuan numerasi juga merupakan kemampuan untuk menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan disebut dengan literasi numerasi. Literasi matematika juga dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang tidak struktur [16]. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah PISA merupakan bagian dari numerasi, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal PISA maka rendah pula kemampuan numerasi mereka.
Pembelajaran Berbasis Numerasi
Keterampilan numerasi dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah maupun di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, misalnya ketika berbelanja, merencana-kan liburan, memulai usaha, membangun rumah, informasi mengenai kesehatan, semuanya membutuhkan numerasi. Informasi-informasi tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk numerik atau grafik. Untuk membuat keputusan yang tepat, siswa harus memahami numerasi. Numerasi adalah kemampuan, kepercayaan diri dan kesediaan untuk terlibat dengan informasi kuantitatif atau spasial untuk membuat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 195
keputusan berdasarkan informasi dalam semua aspek kehidupan sehari-hari [17].
Maka pembelajaran berbasis numerasi merupakan pembelajaran mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matema-tika dalam situasi real sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dasar literasi numerasi: 1) bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya, 2) selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013; dan 3) saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya [14]. Selanjutnya, komponen literasi numerasi dan cakupan matematika dalam kurikulum 2013 tertuang dalam tabel 1 berikut.
Tabel 1. Komponen Literasi Numerasi dalam Cakupan Matematika
Kurikulum 2013
Komponen Literasi Numerasi Cakupan Matematika Kurikulum 2013
Mengestimasi dan menghitung dengan
bilangan bulat
Bilangan
Menggunakan pecahan, desimal, persen, dan
perbandingan
Bilangan
Mengenali dan menggunakan pola dan relasi
Bilangan dan Aljabar
Menggunakan penalaran spasial Geometri dan Pengukuran Menggunakan pengukuran Geometri dan Pengukuran
Menginterpretasi informasi statistik
Pengolahan Data
Namun pada realitamya dalam pembelajaran, guru masih
banyak yang belum memenuhi beberapa komponen literasi numerasi pada tabel diatas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Farihah et al. yang menyatakan beberapa sekolah di Jember belum menerapkan pembelajaran berbasis literasi numerasi matematika. Mereka tidak mentransfer dan mengajarkan konten matematika dengan menggunakan soal-soal realistik. Sebelum pandemi Covid-19, hanya dua sekolah di bawah enam sekolah yang menerapkan metode pembelajaran tersebut lebih dari 25% untuk setiap tahun ajaran.
196 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Sedangkan empat sekolah lainnya hanya menerapkan metode tersebut di bawah 15%. Persentase tersebut semakin rendah selama pandemi ini. Semua sekolah hanya menggunakan literasi matematika di kelasnya hanya di bawah 15% [14].
Pembelajaran Berbasis Online di Era New Normal
Di era pandemi COVID-19 ini tentunya tidak memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran secara face to face atau secara langsung, mungkin setidaknya bisa dilakukan dengan jarak jauh atau virtual yaitu pembelajaran secara online dengan melakukan live e-learning melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom yang merupakan media berbasis aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk wadah pembelajaran. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Farihah et al. pada sekolah berbasis Islam yang menemukan bahwa secara online dengan melakukan live e-learning melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia [14] seperti yang terklihat pada tabel 2 berikut
. Tabel 2. Persentase Siswa yang Menggunakan Sumber Daya Online
(relevan dan tidak relevan dengan studi).
Resources Siswa (%) Rata-rata Nilai
Whatsapp 1.00
0.73
0.19
Instagram 0.81 Facebook 0.50
Other websites (irrelevant)
0.60
Email 0.04
0.15
Ruang guru 0.09 Wolfram 0
Wikipedia 0.15 Google (search
engine) 0.25
Brainly 0.29 Other websites
(relevant) 0.18
Terlihat dari tabel 2 di atas bahwa rata-rata siswa yang
menggunakan aplikasi in approriate berkisar 0,73. Sedangkan yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 197
menggunakan aplikasi pendukung untuk kegiatan pembelajaran sebanyak 0,15. Ketika rata-rata ini dibandingkan, sesuai dengan yang tidak sesuai, peneliti mendapat 0,19, hal itu menunjukkan bahwa jumlah aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran jauh lebih sedikit daripada aplikasi yang tidak sesuai.
Problematika Pembelajaran Numerasi di Era Pandemic Covid pada Sekolah Berbasis Islam di Kabupaten Jember
Problematika pembelajaran numerasi yang terjadi di sekolah berbasis Islam di Kabupaten Jember pada era pandemic covid-19 ini antara lain adalah yabg berkaitan dengan kurikulum, fasilitas, pendidikan karakter, dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah numerasi.
Pertama adalah kurikulum. Kurikulum yang ada di kalangan sekolah berbasis Islam ternyata juga menjadi salah satu kendala dalam terselenggaranya pembelajaran berbasis literasi matematika, yang lebih dikenal dengan pembelajaran numerasi. Ada beberapa jenis kurikulum yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Farihah et al pada sekolah berbasis Islam. Setelah melakukan wawancara dengan 18 guru dari enam sekolah yang berbeda, ternyata terdapat sebuah alur penyusunan kurikulum yang merupakan adaptasi dari kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah [14]. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2. Jalur Penyesuaian Kurikulum Pembelajaran
Curriculum 2013
(K13)
Curriculum 2013 (K13)
+
Independent design
IBS type A
Ministry of National Education and
Cultures Ministry of Religious Affairs
Islamic-based schools
(IBS)
IBS type B IBS type C
198 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tampak berdasarkan gambar di atas bahwa ada dua jenis
kurikulum yang ada di lapangan. Dari kurikulum tersebut tampak bahwa ada sekolah Islam yang menggunakan murni kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah, namun ada pula sekolah Islam yang menggunakan kurikulum 2013 dengan modifikasi. Pada jenis kurikulum yang dimodifikasi, peneliti juga menemukan ada dua kurikulum yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan yang dilakukan oleh maisng-masing sekolah. Pada sekolah Islam tipe A, tampak bahwa sekolah ini menggunakan kurikulum yang disedikan oleh pemerintah tanpa ada perbedaan sama sekali. Metode, sumber belajar, dan strategi yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Di sisi lain, terdapat sekolah yang tidak secara murni menggunakan kurikulum 2013 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang nampak pada sekolah Islam Tipe B dan Tipe C. Kurikulum tersebut telah mengalami perubahan, serta penyesuaian sesuai dengan visi misi sekolah. Bahkan mengalami banyak perubahan dalam strategi, dan metode yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi, khsusunya pada pelajaran matematika.
Ternyata modifikasi tersebut berdampak banyak terhadap jalannya pembelajaran matematika dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tampak pada tabel 3 bahwa jumlah jam pelajaran matematika di jenjang sekolah menengah pertama berbasis Islam di jember sangat beragam. Untuk sekolah tipe A, memiliki 5 JP setiap minggu, hal ini sesuai dengan jumlah jam pembeljaran yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional Indonesia. Sedangkan sekolah tipe B, memiliki jumlah pertemuan yang berkurang, yaitu 4 – 5 JP setiap minggu. Sekolah tipe B memiliki rentan, karena ada sekolah dengan struktur kurikulum dan metode pembelajaran yang sama dengan ketetapan jumlah jam pembelajaran yang berbeda. Selain dua tipe di atas, terdapat tipe C, yang mempunyai jumlah pembelajaran matematika yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran yang disediakan oleh pemerintah, yakni hanya 3 – 4 jam pelajaran per minggu.
Jumlah jam pelajaran matematika yang semakin berkurang ini berada pada sekolah Islam yang berbasis pondok pesantren. Pada hakikatnya, ketiga jenis sekolah ini, menggunakan kompetensi yang sama dengan kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional. Namun, jumlah jam pelajaran per minggu menyebabkan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 199
banyak perbedaan pada ketiganya. Tentu saja, pada sekolah tipe C, hal ini berakibat pada tingkat kedalaman materi yang diberikan oleh guru. Guru hanya mampu memberikan materi pada tingkat awal saja, sehingga kedalaman materi sangat jauh berbeda dengan sekolah yang memiliki jumlah jam pelajaran yang lebih banyak. Sehingga, sekolah dengan tipe kurikulum seperti ini membuat guru jarang menggunakan pembelajaran yang berbasis konseptual dan hampir tidak pernah melakukan aktivitas literasi matematika atau pembelajaran matematika berbasis numerasi serta menggunakan masalah-masalah matematika yang bebasis pemecahan masalah sehari-hari (contextual-based problems).
Tabel 3. Perbedaan Kurikulum Matematika di Sekolah SMP Berbasis
Islam di Kabupaten Jember
Aspek Tipe Sekolah
A B C Jumlah jam pembelajaran per minggu
5 JP 4-5 JP 3-4 JP
Tingkat Taks. Bloom dalam Pembelajaran
C1-6 C1-6 C1-4
Penggunaan Konteks dalam pembelajaran
Biasa Jarang Sangat jarang
Aktivitas Pembelajaran
Berbasis proses dan hasil
Berbasis proses dan hasil
Berbasis hasil
Strategi pembelajaran yang digunakan
Mixed method (berpusat pada guru dan siswa)
Mixed method (berpusat pada guru dan siswa)
Berpusat pada guru +
drill
Sebelum pandemi covid-19, hanya dua dari enam sekolah yang
menjadi sampel dalam penelitian ini. Itu pun dilakukan oleh sekolah sebanyak 25% dari total materi yang ada dalam satu tahun akademik. Sedangkan empat sekolah lainnya hanya melakukan pembelajara berbasis konteks kurang dari 15% dari total materi yang ada, atau
200 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bahkan tidak melakukan pembelajaran berbasis kontekstual. Jumlah ini semakin berkurang pada masa pandemi covid-19 ini, sampai mencapai maksimal 15% dari total materi matematika yang distandarkan oleh kemendiknas yang diajarkan dengan menggunakan context-based problem.
Tampak jelas pada tabel 3 di atas, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya pada jumlah jam pelajaran per minggu. Ini berdampak jauh pada berbagai aspek, yang pertama adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pada sekolah tipe A dan B masih mempunyai pola yang sama, yaitu menggunakan mixed method, teacher center dengan menggunakan aplikasi zoom atau mengupload video pembelajaran di youtube, serta menggunakan students center, yaitu membiarkan siswa mencari, menemukan dan melakukan aktivitas pembelajaran dengan diskusi dengan teman dan pihak lain melalui pemantauan guru. Namun sangat berbeda dengan sekolah dengan tipe C. Mereka cenderung menggunakan teacher center dalam menjelaskan materi, karena dirasa waktu yang sangat kurang dalam menjelaskan. Tak hanya itu, bahkan ketika guru dalam keadaan terdesak, guru mau tidak mau harus melakukan pembelajaran berbasis drill, bukan conceptual based learning sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini dilakukan karena sekolah menghendaki agar nilai ujian nasional mereka tetap bagus dengan waktu pembelajaran yang sangat terbatas. Pembelajaran teacher center di sekolah tipe C ini sangat mungkin dilakukan di era pandemi, karena sekolah tersebut adalah sekolah yang berbasis pondok pesantren.
Aspek kedua yang terdampak adalah tingkat kedalaman materi yang disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Pada sekolah tipe A dan B, masih menggunakan tingkat taksonomi bloom yang hampir merata dalam pembelajaran matematika mereka, mulai dari komponen C1 sampai C6. Sedangkan pada sekolah tipe C, tingkat kedalaman materi yang disampaikan sudah jauh berkurang, hanya mampu menerapkan kemampuan C1 sampai C4. Hal ini sangat bertentangan dengan kaidah pembelajaran yang baik dari kemendikbud, bahwa seorang anak harus belajar pada tingkat C1 sampai C6.
Kedua adalah fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas yang ternyata sangat berperan dalam pembelajaran matematika berbasis literasi di era pandemi ini, salah satunya adalah koneksi internet yang sangat beragam. Aspek ini merupakan aspek yang sangat krusial bagi terlaksananya pendidikan berbasis online [18]. Data yang diperoleh
New Normal, Kajian Multidisiplin | 201
dalam penelitian yang dilakukan di sekolah berbasis Islam di Kabupaten Jember yang diambil 126 responden seperti tampak pada diagram 3 berikut.
Gambar 3. Kualitas internet di Kabupaten Jember
Dapat dilihat dari gambar 3 di atas bahwa kualitas internet yang dimiliki oleh 126 siswa/santri di Kabupaten Jember masih didominasi dengan kualitas yang jelek, bahkan ada yang memiliki sangat jelek. Barulah prosentase tersebut disusul dengan prosentase cukup. Dari data tersebut, dapat diperoleh rasio antara yang memiliki koneksi baik dan buruk sebesar 1.6. Hal tersebut menunjukkan internet koneksi dalam pembelajaran daring masih buruk dan belum memadai. Dube mengatakan bahwa, untuk mendukung pembelajaran online, pemerintah daerah harus memegang peranan penting. Siswa dan guru harusnya mendapat akses yang baik dalam pembelajaran berbasis online ini [18].
Selain itu, ada kendala lain yang dihadapi oleh siswa pada sekolah berbasis keIslaman di Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembelajaran berbasis online, diantaranya adalah keberadaan hand-phone yang mendukung, kepemilikan komputer, dukungan orang tua, dan yang terberat adalah kondisi ekonomi orang tua. Data tersebut diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada siswa berbasis skala likert, yang tampak pada tabel 4 berikut.
1223
3539
17
Internet Connection Quality
very good
good
moderate
bad
202 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tabel 4. Siswa yang punya Kendala Berdasarkan Empat Aspek
Skala
Aspek
Keberadaan HP
Kepemilikan Komputer
Kondisi ekonomi orang
tua
Dukungan orang tua
5 24 5 7 10 4 35 19 29 25 3 37 71 24 49 2 20 12 32 25 1 12 19 34 17
Total 126 126 126 126
Fasilitas pertama, keberadaan handphone, tidak menjadi masalah
yang berarti di Kabupaten Jember. Hal ini diebabkan jumlah siswa yang meilikinya masih terdistribusi hampir merata. Hal ini juga terjadi pada keberadaan komputer/laptop, karena keberadaan handphone masih mendominasi. Sehingga kepemilikan laptop/komputer masih bisa dibantu dengan kepemilikan handphone yang mendukung. Namun, akan sangat tampak berbeda aspek tersebut ketika berbicara tentang kondisi ekonomi. Dari tabel 4 tersebut tampak bahwa orang tua yang memiliki pendapatan rendah jauh lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang memiliki pendapatan tinggi, sekitar 66 banding 36. Hal ini juga terjadi pada dukungan orang tua. Tampak dari tabel tersebut bahwa ada 42 siswa yang berada di bawah skala dua. Hal ini menunjukkan bahwa, orang tua belum mendukung pembelajaran sepenuhnya bagi mereka. Artinya, ketika siswa berada di rumah, siswa tersebut mempunyai tanggung jawab lain yang harus dikerjakan selain melaksanakan tugas pembelajaran.
Guerrero menjelaskan bahwa memang perkembangan teknologi dalam pembelajaran sangat menguntungkan di beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain fleksibiltas terkait dengan lokasi, waktu, dukungan dan biaya, yang membuat hal tersebut menjadi pilihan dalam memilih online learning. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan. Terlebih Guerrero juga menegaskan bahwa, sebagus apapun online learning system, tetap harus diimbangi dengan desain instruksi pembelajaran yang sangat baik. Barulah hal itu bisa digunakan untuk mengajarkan matematika dan numerasi kepada anak secara bermakna [19].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 203
Ketiga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang tertanam dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran berbasis online ini sangat sulit dikontrol oleh guru. Hal ini tampak saat terdapat pemisah antara nilai matematika yang dimiliki oleh siswa dan tingkat pemahaman yang mereka miliki terkait sebuah konsep. Kedua variabel ini saling berbanding terbalik dikarenakan aspek kejujuran. Pemahaman siswa selama pembelajaran matematika di era pandei covid-19 diperoleh dengan menggunakan agket. Angket tersebut disusun berdasarkan kriteria Likert dengan beberapa modifikasi. Data pemahaman siswa ini diperoleh dari 126 siswa di Kabupaten Jember yang berasal dari enam sekolah berbasis Islam. Angket tersebut diberikan secara langsung kepada siswa dengan menggunakan google form, tanpa adanya intervensi dari guru. Data pemahaman siswa sebelum dan sesudah melalui pembelajaran online pada era pandemi ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut.
Tabel 5. Pemahaman siswa sebelum dan selama pandemi covid-19
Tingkat pemahaman Banyak siswa
Sebelum Selama
(Sangat paham) 19 1 (Paham) 27 12
(Cukup paham) 35 31 (Kurang paham) 25 45 (Tidak paham) 19 37
Total 126 126 Rasio paham dan tidak 1.09 0.16
Dapat dilihat di tabel 5, bahwa rasio paham dan tidak paham
materi matematika yang diajarkan oleh guru sebelum pandemi dan selama pandemi sebesar 1.09 dan 0.16. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman siswa yang cukup signifikan, yaitu dengan adanya selisih sebesar 0.91, untuk mata pelajaran matematika. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat pemahaman antara sebelum pandemi dan selama pandemi. Namun data tersebut tampak sangat berbeda dengan perolehan nilai setelah dilaksanakannya ulangan harian pertama selama pandemi. Data nilai ulangan harian tersebut dapat dilihat pada tabel 6.
204 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Nilai yang diperoleh saat pandemi lebih baik dibandingkan
dengan nilai yang diperoleh saat tidak ada pandemi. Hal ini bertolak belakang dengan tingkat pemahaman siswa. Jumlah siswa yang melampaui ketuntasan minimal matematika (KKM) lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Tampak dari tabel 3 bahwa perbandingan siswa yang lulus dan tidak lulus KKM meningkat secara signifikan dari 2.42 menjadi 3.17 dari sebelum pandemi dan selama pandemi. Terdapat kenaikan sebesar 0.75 dari rasio tersebut. Terlebih, selama pandemi, tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah 65 dalam uulangan harian mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan tingkat pemahaman siswa. Setelah mendapatkan data tersebut, peneliti mencoba mencari informasi lebih lanjut terkait dengan jawaban siswa. Ternyata 0.9 siswa meminta bantuan untuk mengerjakan ulangan harian yang diadakan oleh sekolah.
Tabel 6. Nilai ulangan harian sebelum pandemi dan selama pandemi covid-19
Rentang nilai Jumlah siswa
Sebelum Selama
95 – 100 28 27 85 – 94 26 34 75 – 84 33 53 65 – 74 22 12
Dan lain-lain 17 0
Total 126 126 Rasio lulus terhadap tidak 2.42 3.17
Kebanyakan dari mereka meminta bantuan guru privat, yang
dipanggil ke rumah untuk membantu proses belajar, atau bahkan dibantu oleh orang tua, dan saudara siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan anak selama pembelajaran di era pandemi ini masih berorientasi hasil akhir, bukan lagi suatu proses. Setelah melalui wawancara, guru ternyata juga mengalam kebingungan, karena tidak bisa mengontrol sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Apakah benar-benar dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain.
Hasil ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Guerrero. Dia mengatakan bahwa konsep pembelajaran matematika
New Normal, Kajian Multidisiplin | 205
online sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Dia menunjukkan, dalam penelitiannya, bahwa tujuan pembelajaran yang ia tetapkan juga dapat tercapai [19]. Sejalan dengan hasil tersebut, O’Donoghue juga mendukung apa yang dikemukakan Guerrero. Namun, terdapat sedikit perbedaan. Ia menjelaskan bahwa pem-belajaran matematika online tetap efektif untuk kelas atas, bukan pada kelas bawah. Hal ini disebabkan, karena siswa pada kelas atas sudah mampu bertanggungjawab atas diri mereka sendiri terkait dengan aktivitas pembelajaran mereka [20]. OECD juga mengatakan bahwa program OECD terkait dengan PISA saat ini mungkin tidak dapat diakses oleh beberapa negara dikarena fasilitas online leaning system mereka [21].
Kempat adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah numerasi di era new normal masih sangat terbatas. Kemampuan tersebut tampak saat siswa menyelesaikan masalah numerasi yang nampak pada gambar 4.
Dari gambar 4,5 dan 6, siswa S1 menyelesaikan masalah nomor 2 terkait dengan membaca grafik. Dari gambar tersebut tampak bahwa siswa tersebut mampu memformulasikan dan merepresentasikan masalah dan informasi yang terdapat dalam soal numerasi. Hal ini dilakukan siswa dengan cara menuliskan ulang jumlah pengunjung yang meninggalkan sejak pukul 08.00 sampai 13.00, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang jelas, yaitu = 120, 84, 102. 97, 50, 123 dan sseterusnya. Gambar 4. Masalah Numerasi yang Digunakan dalam Mengukur Kemampuan Numerasi Siswa (Soal no 2)
206 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tanda sama dengan disini menunjukkan bahwa siswa paham adanya relasi antara dua objek. Deskripsi pekerjaan siswa pada sesi ini mampu untuk menangkap informasi yang ada dan membuat hubungan antara variabel yang ada. Terlebih, S1 juga memenuhi semua indikator penilaian ketercapaian penyelesaian masalah karena dia dapat dikatakan berhasil dalam memilih strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Strategi yang digunakan S1 sebenarnya hanya mengkaitkan konsep matematis yang ia miliki. Selama wawancara ia dapat menjelaskan bahwa strategi yang digunakan cukup sederhana, yaitu menjumlahkan semua banyak pendatang pada rentan waktu tertentu, lalu mengurangkan dengan jumlah pendatang yang meninggalkan objek wisata, yaitu 𝟏𝟐𝟎 − 𝟎 = 𝟏𝟐𝟎𝟏𝟐𝟎 = 𝟖𝟒 = 𝟐𝟎𝟒.
Dalam meneyelsaikan masalah numerasi di atas, siswa menggunakan berbagai strategi dan kreativitas. Soal tersebut diberikan secara daring, dengan pengerjaan yang daring pula. Hasil pengerjaan tersebut di kirimkan pada peneliti.
Gambar 5. Hasil Pekerjaan Siswa
Gambar 6. Hasil Pekerjaan Siswa S1
New Normal, Kajian Multidisiplin | 207
Berikutnya S1 menginterpretasikan hasil perhitungannya, namun di akhir ia mengalami kegagalan dalam melakukan operasi sehingga mendapatkan penyelesaian masalah yang tidak tepat. Berdasarkan penelitian Sari, et al. masalah PISA yang berbasis konteks memiliki tingkat kesalahan yang paling banyak pada penulisan jawaban akhir dan pemahaman konteks itu sendiri [14].
Ternyata jawaban S1 tersebut juga sama dengan jawaban siswa lain. Setelah dilihat ternyata memiliki kesamaan yang mutlak, artinya melakukan plagiasi penyelesaian masalah. Setelah dilakukan wawancara kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan hanya dapat menjelaskan apa yang tertulis saja. Namun ketika ditanya alasan kenapa menulis penyelesaian tersebut, subjek cenderung tidak menjawab dan membiarkan percakapan via online berlalu begitu saja. Peneliti menangkap bahwa ada kecurangan dalam proses penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan karena, memang Guru belum menerapkan sistem penilaian yang ketat dan dapat terkontrol, sehingga masih banyak kemungkinan siswa untuk melakukan kecurangan seperti plagiarisme.
Penutup
Ada dua faktor yang mempengaruhi kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi program numerasi internasional di masa pandemic covid-19, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada aspek internal, ada beberapa hal yang menjadi kendala: 1) Tersedianya tiga jenis kurikulum yang merupakan hasil modifikasi dari kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kurikulum ini tentu saja berakibat pada bentuk pembelajaran yang ada di kelas, 2) Terdapat kesenjangan antara yang telah dipahami anak dan nilai yang mereka peroleh sebagai hasil evaluasi pembelajaran. Kesenjangan (perbedaan) ini terjadi akibat ketidakjujuran siswa di Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran matematika. Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbandingan yang berbalik antara pemahaman dan nilai siswa. Sedangkan faktor eksternal antara lain: 1) Ketersediaan sarana koneksi internet di Kabupaten Jember belum cukup baik, sehingga sering menyulitkan siswa, 2) Adanya focus pembelajaran yang terpecah, karena siswa cenderung membuka aplikasi yang tidak relevan dengan pembelajaran. Dari fakta tersebut, dibutuhkan sebuah formula pembelajaran matematika berbasis numerasi untuk peserta didik Indonesia di era pandemic ini, sehingga dapat diakses oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.
208 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Rujukan
[1] OECD. Learning Mathematics for Life: A Perspective from PISA. Paris: OECD Publishing. 2009.
[2] OECD. PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science. (Volume 1). Paris: PISA- OECD Publishing. 2013.
[3] P. Wiedarti, et al., Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016.
[4] OECD. PISA 2015; PISA Results in Focus. Paris: PISA- OECD Publishing. 2016.
[5] Center for Systems Science and Engineering (CSSE). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 2020, [online]. Available: https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFmHrb0r60xc_y3rCq3xmp0_-hr3iSmvY5TqDC_tOQNPyZKNV1MCprBoCspoQAvD_BwE
[6] L. Sun, Y. Tang, & W. Zuo Coronavirus pushes education online. Nature Materials, 20200205. 2020 [online], Available: https://doi.org/10.1038/s41563-020-0678-8
[7] K. Goldschmidt & P. D. Msn. The COVID-19 pandemic : Technology use to support the wellbeing of children. Journal of Pediatric Nursing, xxxx, 3–5. 2020 [online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.013
[8] W. Bao. COVID-19 and online teaching in higher education : A case study of Peking University. March, 113–115. 2020. [online]. Avaivable: https://doi.org/10.1002/hbe2.191
[9] U.Verawardina, L. Asnur, A. L. Lubis, & Y. Hendriyani. Reviewing Online Learning Facing the Covid-19 Outbreak. 12(3), 385–392. 2020
[10] S. Ahmed, M. Shehata, & M. Hassanien. Emerging Faculty Needs for Enhancing Student Engagement on a Virtual Platform. MedEdPublish,15. 2020 [online]. Available: https://doi.org/https://doi.org/10.15694/mep .2020.000075.1
[11] S. Gunawan, N. M. Y., & Fathoroni. Variations of Models and Learning Platforms for Prospective Teachers During the COVID-19 Pandemic Period. Indonesian Journal of Teacher Education, I (2) 61-70. 2020
New Normal, Kajian Multidisiplin | 209
[12] T. Obiakor & A. Adeniran. Covid-19 : Impending Situation Threatens To Deepen Nigeria ’ S Education Crisis. Center For The Study Of The Economies Of Africa. 2020.
[13] A. Purwanto, R . Pramono, M. Asbari, P. B. Santoso, L . M . Wijayanti, C . C . Hyun, & R. S. Putri, Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. Journal of Education, Psychology, and Counseling, 2, 1–12. 2020
[14] U. Farihah, Online Learning System during Pandemic Covid-19 at Supporting Mathematics Literacy: Problem Faced by Islamic- Based School High Level at Jember. Paper yang telah dipresentasikan pada The 4th International Conference on Combinatoris, Graph Theory, and Network Topology. 22-23 Agustus 2020.
[15] Goos, M., Dole, S., & Geiger, V. Improving Numeracy Education in Rural Schools: A Professional Development Approach. Mathematics Education Research Journal, 23 (2), 129. 2011
[16] M. R. Mahmud & I. M. Pratiwi, Literasi Numerasi Siswa dalam Pemecahan Masalah Tidak Terstruktur. Kalamatika: Jurnal Pendidikan Matematika, 4 (1), 69-88. 2019. [online]. Available: DOI:https://doi.org/10.22236/KALAMATIKA.vol4no1.2019pp69-88/http://kalamatika.matematika-uhamka.com/index.php/kmk/article/view/331
[17] Alberta, Literacy and Numeracy Progressions. 2018 [Online]. Available: https://education.alberta.ca/literacy-and-numeracy/
[18] B. Dube, Rural Online Learning in the Context of COVID-19 in South Africa: Evoking an Inclusive Education Approach. Multidisciplinary Journal of Educational Research. 10 (2) 2020.
[19] A. J. M. Guerrero et al. E-Learning in the Teaching of Mathematics: An Educational Experience in Adult High School. Mathematics. 2020. [online]. Available: www.mdpi.com/journal/mathematics
[20] J. O’Donoghue, A Comparison of the Advantages and Disadvantages of IT Based Education and the Implications Upon Student. Number 9. Interactive Educational Multimedia. 2004. [online]. Available: http://www.ub.es./multimedia/iem,
[21] OECD, Supporting the continuation of teaching and learning during the Covid-19 pandemic. 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 211
Bab 14
Menakar Kesejahteraan Subjektif Guru pada Masa Adaptasi Baru Erita Yuliasesti Diah Sari17, Iqhsan Eko Setiawan2
Pengantar
Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan, apapun profesinya akan selalu mengalami proses psikologis secara alamiah, mengikuti dinamika pekerjaan tersebut. Individu akan mengembangkan pola pikir dan perasaannya sebagai salah satu modal untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang ditekuni. Hal ini tidak lain agar individu mampu bekerja optimal dan mencapai tujuan, karena pencapaian tujuan akan berdampak positif pada efektivitas [1]. Seseorang yang bekerja memerlukan banyak usaha, motivasi dan dukungan lingkungan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi bersama dengan dukungan sosial akan mampu mentransformasikan individu pada keterikatan pekerjaan [2].Aspek kognitif, afektif dan psikomotor menjadi andalan agar individu menjadi utuh sehingga tidak merasa terbebani dengan tugas. Cara pikir dan perasaan positif menjadi hal penting, dan inilah yang akan mendorong munculnya kesejahteraan psikologis bagi individu.
Sejahtera adalah istilah yang sangat subjektif, perseptual dan penuh interpretasi yang beraneka ragam. Setiap orang hampir dipastikan menginginkan sejahtera dalam hidupnya, dapat berupa sejahtera secara fisik atau psikologis. Namun demikian, ukuran sejahtera tidak mudah untuk didefinisikan. Semua ukuran sejahtera merupakan kesepakatan yang dapat mengalami perubahan, sehingga dipastikan bahwa ukuran sejahtera adalah subjektif. Mengukur kesejahteraan juga harus jelas apa yang diukur dan bagaimana data yang dihasilkan akan diinterpretasi, agar mendapatkan asesmen yang adil dan valid [3].
Profesi guru di Indonesia saat ini menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan sekaligus menjadi sorotan masyarakat. Hal ini terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung, meskipun sebagian masyarakat telah mencoba menerobos dan membuka era adaptasi baru. Dunia pendidikan menjadi krusial pada masa seperti
17 Dr. Erita Yuliasesti Diah Sari,S.Psi.,M.Si, Magister Psikologi Profesi Universitas Ahmad
Dahlan, Yogyakarta 2 Iqhsan Eko Setiawan, Magister Psikologi Profesi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
212 | New Normal, Kajian Multidisiplin
ini karena di satu sisi menjadi pilar pembangunan manusia Indonesia, namun di sisi lain menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi. Siap atau tidak, seluruh komponen dunia pendidikan harus bersedia melewati kendala dan berupaya mencari solusi. Guru menjadi bagian penting, karena berfungsi sebagai pendidik sekaligus memenuhi eksistensinya sebagai individu yang memiliki berbagai kebutuhan dan tuntutan. Terkait peran dalam pembangunan kesejahteraan guru menjadi faktor penting pendidikan di masa depan [4]. Bekerja dan tetap produktif bagi guru pada masa adaptasi baru memerlukan upaya keras karena harus menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan, baik dari sekolah, maupun masyarakat. Tuntutan yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan seperti penggunaan teknologi komunikasi secara masif untuk menunjang pembelajaran daring. Selain itu problema beban kerja juga semakin bertambah. Disinilah peran kesejahteraan psikologis diperlukan agar guru dapat melakukan pekerjaan tanpa beban sehingga mendapatkan hasil optimal. Penelitian [5], bahkan melaporkan bahwa pada masa pandemik, guru merasa ada sisi baik dari situasi ini, yakni tertantang sekaligus merasa terlatih untuk menghadapi siswa maupun orang tua dengan metode daring.
Kesejahteraan subjektif dimaknai secara luas oleh para ahli, dan tokoh yang paling berpengaruh adalah Diener, yang juga menyebut dengan istilah kebahagiaan [6]. Istilah populer untuk kesejahteraan subjektif ini adalah subjective well-being (sering disingkat dengan SWB). Istilah ini merujuk pada evaluasi kognitif dan afek seseorang tentang hidupnya. Evaluasi tersebut meliputi reaksi emosional terhadap berbagai kejadian yang dialami yang sejalan dengan penilaian kognitif terhadap kepuasan dan pemenuhan hidup. Diener dalam ulasannya mengatakan bahwa afek positif yang tinggi, afek negatif yang rendah, dan kepuasan hidup yang tinggi merupakan gambaran dari tingginya kesejahteraan subjektif [7]. Dapat dikatakan bahwa istilah ini menunjukkan penilaian seseorang terhadap kualitas kehidupannya sebagai sesuatu yang diharapkan dan merasakan perasaan yang menyenangkan [8]. Kesejahteraan psikologis ini juga disebutkan sebagai persepsi dari respon emosional terhadap pengalaman positif dan negatif, dan evaluasi kognitif terhadap kepuasan hidup [9].
Konstrak kesejahteraan subjektif dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu evaluasi kognitif dan evaluasi afek [6]. Pertama, dimensi kognitif dikatakan sebagai evaluasi dari kepuasan hidup, yang dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menikmati pengalaman-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 213
pengalaman yang dimiliki dengan kegembiraan. Evaluasi ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Evaluasi Kepuasan Hidup Secara Global (Global Judgements of Life Satisfaction) dan kepuasan dalam domain khusus. Evaluasi kepuasan hidup secara global adalah penilaian individu secara menyeluruh tentang kepuasan hidupnya. Penilaian ini dimaksudkan untuk mewakili penilaian yang luas dan reflektif yang dilakukan seseorang mengenai kehidupan. Evaluasi kepuasan hidup secara global ini menjadi rujukan temuan penelitian tentang kesejahteraan subjektif [10]. Kedua, dimensi afek, yang merefleksikan pengalaman dasar dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup seseorang dengan mood dan emosi terhadap peristiwa yang menunjukkan bahwa hidup berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dimensi tersebut ditunjukkan dengan tingginya afek positif dan rendahnya afek negatif. Afek positif meliputi berbagai macam perasaan positif diantara-nya, kepercayaan diri, minat, harapan, kebanggaan, dan suka cita. Afek negatif meliputi berbagai macam perasaan negatif diantaranya kecewa, marah, benci, rasa bersalah, takut dan kesedihan.
Terdapat banyak variabel yang terkait dengan kesejahteraan subjektif dan menjadi topik dari berbagai penelitian. Subjek penelitian umumnya sangat bervariasi yang menunjukkan keluasan penggunakan alat ukur kesejahteraan subjektif. Kajian literatur yang dilakukan [11] menemukan beberapa variabel penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif, yaitu modal psikologis, burnout, penggunaan teknologi, dan dukungan sosial. Kajian lain dari [12] menemukan bahwa kegembiraan, antusiasme, perasaan damai, kebersyukuran, kebahagiaan berkaitan dengan kesejahteraan subjektif, khususnya kepuasan dalam hidup. Secara khusus [13] meneliti kesejahteraan subjektif pada usia remaja, dan menemukan bahwa dukungan sosial dari teman akan meningkatkan kesejahteraan subjektif. Penelitian [14] dengan berbagai ragam usia juga menemukan bahwa dukungan sosial berkontrusi terhadap kesejahteraan subjektif. Penelitian [15] pada guru Pendidikan anak usia dini menemukan bahwa dukungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif. Dukungan sosial ini dapat memper-baiki kondisi stres yang datang dari pekerjaan, sehingga emosi negatif menjadi turun, dan emosi positif meningkat. Jika guru memiliki lingkungan baik dengan dukungan sosial tinggi, maka emosi positif dapat meningkat. Lingkungan secara fisik ternyata juga dapat men-dorong peningkatan kesejahteraan subjektif, misalnya lingkungan
214 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tempat tinggal, akses mendapatkan layanan kesehatan, atau hubungan dengan tetangga sekitar rumah [16].
Selain dukungan sosial, kebersyukuran, dan pemaafan, faktor kepribadian juga memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan subjektif, khususnya pada kepuasan hidup seperti hasil penelitian [17]. Individu yang bersedia memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi dan bersyukur akan merasa puas dalam hidupnya dan merasakan kebahagiaan. Rasa sejahtera juga tercipta karena ada factor kepribadian yang terlibat di dalamnya, yaitu keterbukaan, kehati-hatian, ekstroversi dan persetujuan. Stabilitas emosi yang rendah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini adalah kepuasan hidup. Selain memafkan diri sendiri, memaafkan orang lain juga mampu meningkatkan kesejah-teraan subjektif, karena memaafkan orang lain akan mendatangkan kedamaian dan mempererat hubungan dengan orang lain [18]. Rasa bersyukur juga dapat dikaitkan dengan kualitas tidur dan proses biologis seseorang selain juga meningkatkan kesejahteraan subjektif. Penelitian Jackowski [19] menunjukkan hal tersebut melalui intervensi kesyukuran.
Paparan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif dapat dikaitkan dengan banyak variable, baik individual maupun situasional. Karakter konstrak yang fleksibel membuat kesejahteraan subjektif dapat digunakan untuk asesmen berbagai kalangan. Penelitian ini secara spesifik mengambil profesi guru dengan melihat aspek-aspek demografi yang ada, serta menguji apakah ada perbedaan kesejaheraan subjektif berdasarkan aspek demografi tersebut.
Pembahasan
Penelitian ini melibatkan partisipasi 146 orang guru TK, SLP dan SLTA yang berasal dari beberapa kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mengingat kondisi yang tidak memungkin mengambil data secara langsung, maka pengambilan data dilakukan dengan Google form yang dirancang sedemikian rupa agar mudah dipahami responden. Data diambil dalam rentang bulan Juli-Agustus 2020. Kesediaan menjadi responden (informed consent) dilampirkan pada formulir. Jika calon responden bersedia maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan, jika tidak bersedia, responden dapat membatalkan keikutsertaannya. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Subjective well-being yang diadaptasi dari instrumen Diener versi 17 item, yang terdiri dari dimensi Afek positif sebanyak 6 item, Afek negatif sebanyak 6 item dan dimensi Kepuasan hidup sebanyak 5. Setelah melalui proses adaptasi, didiskusikan, dan diujicobakan, diperoleh instrumen pene-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 215
litian dengan item yang utuh dengan koefisien reliabilitas masing-masing sebesar 0.789, 0.792 dan 0.744. Keseluruhan data penelitian dianalisis dengan program SPSS IBM versi 26. Sebelum siap dianalisis lanjut, data penelitian distandarisasi untuk memperoleh skor kesejah-teraan subjektif. Skor mentah yang diperoleh terlebih dahulu diubah menjadi nilai standar z (z-score) kemudian skor t (t-score), sehingga diperoleh skor SWB terstandar.
Melalui deskripsi data demografi, diperoleh hasil berikut:
Gambar 1. Kategori berdasarkan sekse Gambar 2. Kategori berdasarkan usia
Grafik pada gambar 1 menggambarkan responden yang
didominasi oleh guru wanita, sedangkan pada gambar 2 ditunjukkan
kelompok usia yang paling banyak ditemukan adalah kelompok usia 31-
40 yang merupakan usia muda dan produktif.
Grafik pada gambar 3 menunjukkan tingkat pendidikan guru
yang didominasi oleh lulusan sarjana, sedangkan lulusan Master tidak
mencapai separuhnya. Pada gambar 4 nampak bahwa masa kerja guru
sebagian besar ada pada kelompok usia masa kerja 11-20 tahun, namun
ditemukan juga kelompok masa kerja di atas 30 tahun, yang diduga
dimiliki oleh guru-guru senior.
216 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Gambar 3. Kategori berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja
Gambar 4. Kategori berdasarkan level sekolah
Berdasarkan hasil kategorisasi variabel kesejahteraan subjektif,
ditemukan bahwa mayoritas responden memiliki kesejahteraan subjektif
dalam kategori sedang, dan jumlah yang lebih kecil termasuk kategori
rendah dan tinggi. Gambaran kategori tersebut dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:
Gambar 5. Kategori kesejahteraan subjektif (SWB)
New Normal, Kajian Multidisiplin | 217
Hasil kategori di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, guru-guru merasakan kesejahteraan dirinya dalam taraf sedang. Hal ini berarti sebagian besar guru selama masa adaptasi baru merasakan hal-hal positif dan juga negatif. Guru juga merasa cukup puas dalam kehidupannya, meskipun dapat dikatakan tidak tinggi tetapi juga tidak rendah. Situasi yang berbeda akibat pandemi diterima dengan perasaan yang netral. Tugas guru sebenarnya sama banyaknya dengan ketika sebelum pandemi, hanya saja kemudian terjadi perubahan yang memaksa guru beradaptasi dengan situasi baru. Teknologi menjadi media utama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru cukup mampu menghadapi situasi baru dengan menampilkan respon netral, tetap memiliki perasaan positif, dan merasakan kepuasan dalam hidup.
Berikutnya, untuk melengkap data, diperlukan ekplorasi kesejahteraan subjektif melalui uji statistik. Teknik yang dipilih adalah uji beda untuk melihat perbedaan rerata beberapa kelompok. Tahap ekplorasi dimulai dengan memenuhi sejumlah persyaratan seperti uji normalitas, yang dimaksudkan untuk melihat apakah data yang diperoleh menunjukkan sebaran normal. Kelompok yang diuji adalah kelompok berdasarkan sekse, tingkat pendidikan, usia, masa kerja dan level sekolah.
Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa kelompok sekse memiliki nilai signifikansi 0.2 (lebih besar dari 0.05) yang berarti data dikatakan normal. Sebaran data kelompok tingkat pendidikan, masa kerja dan usia juga menunjukkan data normal dengan rentang signifikansi 0.109 sampai 0.2. Kelompok level sekolah menunjukkan sebaran data tidak normal pada pilihan lainnya dengan nilai signifikansi di bawah 0.05. Pada data normal, uji berikutnya dapat dilanjutkan, namun data yang tidak normal harus diperlakukan berbeda. Mengikuti hasil tersebut, maka dilakukan uji Kruskal Wallis sebagai alternatif uji anova, dan diperoleh Asymp signifikansi pada nilai 0.828 (lebih besar dari 0.05) yang berarti tidak ada perbedaan kesejahteraan subjektif di antara kelompok guru pada level sekolah. Level sekolah dalam hal ini dilihat dari level guru TK, SD, SLTP dan SLTA dan kelompok yang tidak diketahui. Merujuk hasil tersebut, semua guru pada semua level sekolah tidak mengalami perbedaan dalam perasaan positif, negatif maupun mempersepsi kepuasan hidupnya. Pada masa adaptasi ini kemungkinan semua guru merasakan hal yang sama, karena harus menghadapi peristiwa yang dampaknya sangat luas. Baik perasaan
218 | New Normal, Kajian Multidisiplin
positif maupun negatif kemungkinan juga muncul bersamaan, dan seiring dengan kepuasan hidup yang dirasakan.
Kembali pada persyaratan, setelah melalui uji normalitas, analisis dilanjutkan dengan melakukan uji beda sekaligus mencermati homogenitas varian. Berdasarkan uji homogenitas, diketahui varian semua data homogen karena memiliki nilai di atas 0.05. Dengan demikian, maka tahap uji beda dapat dilanjutkan. Pada saat dilakukan uji beda terhadap kelompok yang ada, ditemukan bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok yang diuji. Semua nilai signifikansi yang diperoleh berada di atas 0.05, yang berarti menyatakan tidak ada perbedaan kesejahteraan subjektif pada semua kelompok responden. Sebagai contoh hasil uji beda kelompok pria dan wanita menghasilkan nilai signifikansi 0.862. Uji beda pada kelompok usia, menunjukkan nilai signifikansi 0.247 yang menunjukkan tidak ada beda kesejahteraan subjektif pada kelompok usia responden. Demikian juga dengan kelompok masa kerja, juga tidak dapat menunjukkan perbedaan karena nilai signifikansinya 0.302.
Hasil uji beda menunjukkan bahwa pada guru pria maupun wanita, pada semua usia, baik yang berpendidikan Sarjana maupun Master, pada semua masa kerja dan level sekolah tidak ditemukan perbedaan perasaan positif, perasaan negatif maupun kepuasan hidup selama menjalani masa adaptasi baru. Perubahan yang ada sudah mulai mampu diterima meskipun masa pandemi dapat dikatakan belum selesai. Kecemasan dan rasa ketidaknyamanan yang biasanya dirasakan banyak orang perlahan-lahan mulai memudar dan mengembalikan pada situasi normal dengan adaptasi. Inilah mengapa perasaan positif, negatif maupun kepuasan hidup tidak mengalami penurunan, meskipun pada pencermatan respon awal, ada kelompok responden yang kesejahteraan subjektifnya rendah. Dapat dikatakan guru-guru tersebut cukup mampu bertahan dengan situasi yang ada, dan mampu beradaptasi dengan kondisi baru.
Melihat hasil di atas, perlu ada perhatian pada perluasan aspek yang menjadi pembeda. Faktor demografi nampaknya belum cukup memadai untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, meskipun ada penelitian lain yang sejalan, misalnya [4]. Penelitian lain yang lebih komprehensif misalnya [20] membandingkan kesejahteraan subjektif pada guru wanita dengan melihat aspek lingkungan kerja dan relasi sosial guru. Ditemukan bahwa guru yang berada dalam relasi sosial kuat dan lingkungan kerja yang baik memiliki kesejahteraan subjektif lebih
New Normal, Kajian Multidisiplin | 219
tinggi dibandingkan guru dengan relasi sosial dan lingkungan kerja yang tidak memadai.
Penutup
Masa adaptasi baru memang bukan masa yang mudah, namun juga tetap harus dijalani dengan hati hati. Perasaan positif, perasaan negatif dan kepuasan hidup yang dapat berjalan seiring merupakan potensi positif, agar memperoleh keseimbangan psikologis. Profesi guru merupakan profesi penting dalam tata kehidupan, namun pada saat mengalami tantangan yang cukup besar di masa pandemi, memerlukan ketangguhan bagi pelakunya. Perasaan positif perlu ditingkatkan, perasaan negatf perlu dikrang atau bahkan dihilangkan, dan kepuasan hidup dapat ditingkatkan. Guru tentu saja tidak akan mampu bekerja sendiri, namun harus memanfaatkan jejaring dalam upaya bersama-sama meningkatkan kesejahteraan subjektif. Guru dalam bekerja pada masa pandemik dapat berupaya mengoptimalkan kemampuan psikologisnya, belajar meningkatkan penerimaan diri, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta bersyukur atas situasi yang dialami seharihari. Dengan demikian, kehidupan akan ditanggapi positif, individu merasa puas, dan kesejahteraan dapat dicapai.
Rujukan
[1] T. C. Theo dan K. C. P. Low, “The Impact of Goal Setting on Employee Effectiveness to Improve Organisation,” Journal of Business & Economic Policy, vol. 3, no. 1, pp. 82-97, 2016.
[2] C. M. Kim, S. W. Park, J. Cozart and H. Lee, "From Motivation to Engagement: The Role of Effort Regulation of Virtual," Educational Technology & Society, vol. 18, no. 4, pp. 261-272, 2015.
[3] R. Dodge, A. P. Daly, J. Huyton and L. D. Sanders, "The challenge of defining wellbeing," International Journal of Wellbeing, vol. 2, no. 3, pp. 222-235, 2012.
[4] S. Roy, "Well being of Secondary and Higher Secondary school Teachers," International Journal of Research and Analytical Reviews, vol. 5, no. 3, pp. 1-7, 2018.
[5] I. P. Samuelsson, J. T. Wagner and E. E. Ødegaard, "The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned," International Journal of Early Childhood, vol. 52, pp. 129-144, 2020.
220 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[6] E. Diener, Assessing well-being: The Collected Works of Ed Diener, New York: Springer, 2009.
[7] I. Albuquerque, M. P. de Lima, C. Figueiredo and M. Matos, "Subjective Well-Being Structure: Confirmatory Factor," Social Indicators Research, vol. 105, pp. 569-580, 2012.
[8] R. Veenhoven, "Greater Happiness for A Greater Number Is that possible? If so, how?," in Designing Positive Psychology: Taking Stock and Moving Forward, New York, Oxford University Press, 2011, pp. 396-409.
[9] C. L. Proctor, "Subjective well-being," in Encyclopedia of quality of life and well-being research, Dordrecht , Springer, 2014, pp. 6437-6441.
[10] A. Kapteyn , J. Lee, C. Tassot, H. Vonkova and G. Zamarro, "Dimensions of Subjective Well-Being," Social Indicators Research, vol. 123, pp. 625-660, 2015.
[11] A. Sahai and M. Mahapatra, "Subjective Well-being at Workplace: A Review on its Implications," Journal of Critical Reviews, vol. 7, no. 11, pp. 807-810, 2020.
[12] A. Dirzyte and A. Patapas, "Determinants of Subjective Wellbeing: Lithuanian Case," European Scientific Journal , vol. 11, no. 2, pp. 138-149, January 2015.
[13] A. B. Žganec, K. Lipovcan and I. Hanzec, "The Relationship between Social Support and Subjective Well-Being across," dru[. istra@. zagreb god, vol. 27, pp. 47-65, 2018.
[14] K. L. Siedlecki, A. S. Timothy, S. Oishi and S. Jeswani, "The Relationship Between Social Support," Social Indicators Research, vol. 117, no. 2, pp. 561-576, 2014.
[15] L. H. Ming, C. M. Ju, C. C. Ho and W. H. Tang, "The Relationship Between Social Support And Subjective Well-Being Of Preschool Teachers: Take Age As The Moderator Variable," European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, vol. 4, no. 8, pp. 63-75, 2016.
[16] Y. Liu, M. Dijst and S. Geertman, "The subjective well-being of older adults in Shanghai: The role of residential environment and Individual Resources," Urban Studies, vol. 54, no. 7, pp. 1-24, 2016.
[17] J. D. Datu, "Forgiveness, Gratitude and Subjective Well-Being Among Filipino Adolescents," International Journal for the Advancement of Counselling, vol. 6, no. 3, pp. 262-273, 2014.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 221
[18] M. M. Roxas, A. David and J. R. Aruta, "Compassion, Forgiveness and Subjective Well-Being among Filipino Counseling Professionals," International Journal for the Advancement of Counselling, vol. 41, pp. 272-283, 2019.
[19] M. Jackowska, J. Brown, A. Ronaldson and A. Steptoe, "The impact of a brief gratitude intervention on subjective well-being, biology and sleep," Journal of Health Psychology, vol. 21, no. 10, pp. 1-11, March, 2015.
[20] R. D. Uche and M. E. Ngwu, "Correlates of Subjective Well-Being Among Middle Aged Female Teachers in Public Secondary Schools of Bayelsa State, Nigeria," Advances in Social Psychology, vol. 2, no. 1, pp. 1-5, 2017.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 225
Bab 15
Implementasi Nilai-Nilai Moral Pancasila Dan Perubahan Perilaku di Era Pandemi Covid-19 Abustan18
Pengantar
Tatkala tenunan sosial robek. Saat itulah, tak dapat dipungkiri kita memerlukan Pancasila sebagai simpul perekat. Maka dari itulah, pembangunan manusia Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual –kultural melalui sektor pendidikan yang beriringan dengan fungsi institusional politicaldan fungsi material tehnologikal [1] [3].
Menggaris bawahi peradaban, maka mau tak mau jika ingin memanjurkan nilai-nilai Pancasila haruslah dikristalkan secara efektif dalam ketiga ranah peradaban: tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera [4]..Sejalan dengan itu, meminjam ungkapan John Garner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak mengandung dimensi nilai moral guna menopang peradaban besar.”
Tata nilai adalah fondasi atau cahaya petunjuk yang memberi peta jalan menuju titik tujuan. Karena itu, sehebat apapun pembangunan fisik, agenda program, dan keterampilan yang kita kerahkan tidaklah memberikan nilai tambah yang signifikan. Bahkan justru nilai tersebut bisa melenceng dari jalur yang benar (on the track). Padahal, sebagai nilai fundamental moral public, nilai Pancasila haruslah diinternalisasi dan dioperasionalisasikan penuh kejujuran dengan menjaga konsistensi sikap antara pikiran, perhatian, dan perbuatan (prilaku).Lalu, peradaban suatu bangsa hanya bisa dimanjurkan pula melalui ketepatan tata kelola. James A. Robinson memberi elaborasi lebih jauh hal-ikhwal kegagalan suatu Negara-bangsa bukan karena faktor sumber daya alam atau SDMnya, tetapi lebih pada factor karena “salah urus” alias desain kelembagaan dan tata kelola pemerinthan [1] [3].[5] [8] .
Akibatnya, lembaga tidak berjalan/berfungsi optimal. Sebaliknya relasi antar lembaga menunjukkan ketidakharmonisan dan/atau tidak bersinergi dengan baik. Oleh sebab itu, tata kelola yang baik menjadi kata kunci keberhasilan terwujudnya segala sektor kehidupan bernegara. Bung Hatta sejak tahun 1932 dalam pidatonya,[3].[9] “Ke a rah Indonesia
18 Dr. H. Abustan, Dosen Universitas Islam Jakarta
226 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Merdeka” menegaskan: “Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat .. Inilah arti kedaulatan rakyat”. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tata kelola haruslah bertujuan dan diarahkan untuk kedaulatan rakyat. Terakhr, peradaban untuk maju. Pada tahap ini ditentukan oleh kesanggupan bangsa dalam mengelola kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi penguasaan Negara atas kekayaan alam dan seluruh hajat hidup orang banyak harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. [10].[11].
Atas dasar itulah, segala sesuatunya haruslah kembali kepada “goal” bernegara, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, elemen penting lainnya adalah menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum. Dalam rangka mengokohkan eksistensi negara sebagai Negara hukum (vide Pasal 1 ayat 3 UUDN 1945). Maka, dari tahun ke tahun setiap kali memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni, kita (bangsa Indonesia) kembali disibukkkan berdiskusi/memperbincangkan Pancasila dengan berbagai sebutan: Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila sebagai ideologi dinamis dan terbuka, Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa dll. Dan di tengah situasi keprihatinan bangsa karena sikap pragmatisme dan liberalisasi ekonomi, maka Pancasila kembali “diteriakkan” sebagai bintang penjuru dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga solidaritas sosial dan sikap prilaku tradisional di desa tetap terpelihara tidak tercerabut dari akar budaya. Karena itulah, kemanjuran nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan sekalipun tantangan zaman terus berubah, sebagai acuan sopan santun dan keadaban dalam pergaulan.
Pembahasan
Membangun manusia Pancasila bukan urusan satu mata pelajaran atau tugas seorang guru pendidikan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini memang sangat penting karena memuat berbagai pengetahuan tentang Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945.kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk lembaga-lembaga Negara dan sistem pemerintahan, politik dan demo-krasi, hak dan kewajiban warga Negara, serta perlindungan dan penegakan hukum [11].[13].[14].
Oleh sebab itu, pendidikan formal seharusnya bisa mengajak peserta didik dari masyarakat Indonesia yang dikenal sangat agamisuntuk menyelam lebih dalam dan mendaki lebih tinggi dari
New Normal, Kajian Multidisiplin | 227
sekedar menghafalkan, memahami dan taqlik pada doktri n, symbol, serta ritual keagamaan. Manusia Indonesia yang berketuhanan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ajaran agamanya, tetapi juga mengembangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap warga bangsa yang berbeda iman dan mendukung sesame yang berbeda untuk bisa menjadi penganut agamanya dengan lebih baik. Kerangka acuan dan kerangka dasar ini, menjadi konsep tentang misi atau dakwah sudah semestinya ditelaah dengan lebih mendalam dan tidak tersandera pada penambahan statistik jumlah pemeluk, melainkan pada spiritualitas para pencari kebenaran serta kontribusi terhadap solusi permasalahan masyarakat.
Menggarisbawahi hal tersebut, menunjukkkan bahwa proses menjadi manusia yang adil dan beradab juga terjadi dalam lokus pendidikan. Kurikulum yang berlandaskan Pancasila mesti bebas dari biasa yang mengagungkan satu kelompok masyarakat dan mengederkan kelompok lain. Wawasan nusantara siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi melalui banyak konten-materi tentang suku-suku, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai tradisionil yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Pemahaman tentang keberagaman dan kekayaan budaya nusantara diharapkan bisa mencerahkan anak-anak Indonesia. Dan seyogyanya pula mengajak peserta didik untuk mengolah diri, berinteraksi dengan sesame warga bangsa, demi menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Sebab sila ketiga Pancasila tidak berarti perbedaan individu /kelompok mesti dilebur atau disatukan.
Akan tetapi, sebaliknya tidak menjadi ekstrim seperti politik identitas belakangan ini yang berakibat pada keterbelahan masyarakat melalui eksploitasi kelompok berdasarkan mazhab agama, etnis, suku, dan kelas sosial. Bahkan sampai tahaf yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, terlepas dari berbagai perbedaan persepsi, bangsa Indonesia sudah memilih peta jalan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hikmat kebijaksanaan seharusnya merupakan landasan capaian pembelajaran yang mengarahkan proses kurikulum. Kehidupan berorganisasi siswa, interaksi siwa-guru, dan antar siswa merupakan aplikasi serta ujian dalam Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan.
Untuk itulah, dalam mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, peserta didik perlu menguasai ilmu-ilmu duniawi. Pengajaran dalam kategori imu-ilmu matematika dan pengetahuan alam/sosial serta penguasaan bahasa (daerah, Indonesia
228 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dan asing) bisa membekali dan menumbuhkembangkan wawasan anak dan kecerdasan /keterampilan menghadapi berbagai ketidakadilan dan berbagai bentuk problematika kehidupan. Dengan demikian, pengajaran ilmu-ilmu duniawi ini menjadi asset berharga bagi peserta didik sekaligus mampu menggunakannya bagi kemaslahatan masyarakat luas.
Menggaris bawahi hal tersebut di atas, maka mau tak mau jika ingin memanjurkan nilai-nilai Pancasila haruslah dikristalisasikan dan/atau diimplementasikan secara efektif dalam ketiga ranah peradaban: tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Sejalan dengan itu, meminjam ungkapan John Garner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak mengandung dimensi nilai moral guna menopang peradaban besar.”
Akibatnya, lembaga tidak berjalan/berfungsi optimal. Sebaliknya relasi antar lembaga menunjukkan ketidakharmonisan dan/atau tidak bersinergi dengan baik. Oleh sebab itu, tata kelola yang baik menjadi kata kunci keberhasilan terwujudnya segala sektor kehidupan bernegara. Bung Hatta sejak tahun 1932 dalam pidatonya, “Ke a rah Indonesia Merdeka” menegaskan: “Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Inilah arti kedaulatan rakyat”. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tata kelola haruslah bertujuan dan diarahkan untuk kedaulatan rakyat.
Oleh sebab itulah, peradaban untuk maju pada tahap ini ditentukan oleh kesanggupan bangsa dalam mengelola kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi penguasaan Negara atas kekayaan alam dan seluruh hajat hidup orang banyak harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, tak dapat disangkal/dipungkiri bahwa pembangunan manusia Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-spiritual-kultural melalui sektor pendidikan. Asumsi dasar itulah, segala sesuatunya haruslah kembali kepada “goal” bernegara, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, elemen penting lainnya adalah menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum. Dalam rangka mengokohkan eksistensi negara sebagai Negara hukum (vide Pasal 1 ayat 3 UUDN 1945).
Maka, dari tahun ke tahun setiap kali memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni, kita (bangsa Indonesia) kembali disibukkkan berdiskusi/memperbincangkan Pancasila dengan berbagai sebutan:
New Normal, Kajian Multidisiplin | 229
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila sebagai ideologi dinamis dan terbuka, Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa dll.
Dan di tengah situasi keprihatinan bangsa karena sikap pragma-tisme dan liberalisasi ekonomi, maka Pancasila kembali “diteriakkan” sebagai bintang penjuru dalam menghadapi ujian tersebut, sehingga solidaritas sosial dan sikap prilaku tradisional di desa tetap terpelihara tidak tercerabut dari akar budaya. Karena itulah, kemanjuran nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan sekalipun tantangan zaman terus berubah, sebagai acuan sopan santun dan keadaban dalam pergaulan sebagai refleksi dari perwujudan manusia Pancasila dalam menahan lonjakan kemiskinan di tengah gempuran Pandemi Covid 19 diberbagai wilayah seluruh Indonesia.
Pemerintah Daerah, HAM, dan Keberadaan Pancasila
Pejabat lokal atau pemangku kepentingan yang ada di daerah, setingkat Gubernur, Walikota/Bupati, kini tengah berusaha menahan laju salah satu pandemi terbutuk dalam sejarah modern. Di tengah kondisi ini krisis ini, diperlukan kesediaan/kemampuan penyelenggara Negara in-casu pemerintah untuk bergerak cepat melakukan langkah kordinatif dan/atau kerja koloboratif dengan seluruh stakeholder.
Namun, kenyataan yang ada berbagai upaya pemerintah daerah, dihadapkan pada para pemimpin nasional yang tampaknya tetap berusaha untuk mengelola pemerintahan secara sentralistik, .Padahal, dalam regulasi tentang Pemerintahan Daerah UU 23/2004 yang telah direvisi dalam UU Pemda yang baru UU 23/2014 sudah diberlakukan sebagai “kerangka acuan” bagi praktek desentralisasi dan otonomi daerah (Otda) .Dalam perspektif pemerintahan daerah, daerah adalah kumpulan unit-unit lokal dari pemerintah yang otonom, independen dan bebas dari kendali kekuasaan pusat. Dalam sistem ini pemerintah daerah ini pemerintah daerah meliputi institusi-institusi atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, sangat jelas bahwa masing-masing jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) mengemban amanat untuk mewujudkan kepentingan nasional. Masing-masing jenjang pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Itulah relaitas kondisi pemerintahan saat ini, ketika keadaan darurat terjadi akibat virus corona. Karena itulah, akan menjadi relevan memberikan otoritas masing-masing kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan yang terbaik bagi daerahnya.
230 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Apakah dengan sistem lock down, karantina lokal/parsial, pembatasan sosial skala besar (PSSB), atau karantina wilayah (vide UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan) yang nota bene merupakan produk sendiri pemerintah pusat. Yang pasti, tentu saja, setiap opsi (pilihan) ada konsekwensi-konsekwensi yang menyertainya.
Dengan demikian, pemerintah pusat tidak perlu mewacanakan Darurat Sipil yang belum tentu bisa atasi “terror” Covid 19, tapi malah justru bisa jadi “blunder” terhadap kehidupan demokrasi. Lebih dari itu, darurat sipil bukanlah suatu solusi untuk bisa atasi permasalahan darurat kesehatan yang ada sekarang ini. Akan tetapi, satu-satunya harapan untuk selamat dari krisis ini adalah membangun solidaritas bersama antarwarga. Atau memperkuat relasi pusat-daerah dalam bingkai otonomi daerah di tengah ancaman global Covid-19. Apalagi bertita memprihatinkan terus berkembang dengan banyaknya aparat pemerintah daerah yang terkena virus yang membahayakan ini. Terakhir berita meninggalnya Bupati Morowali Utara diterima dengan perasaan terharu dan duka cita yang mendalam. Diberitakan bahwa proses pemakamannya dilakukan dengan standard-prosedur penanganan Covid-19. Demikian pula, rakyat tidak menunjukkan adanya suatu acara penguburan. Rakyat seluruh wilayah Morowali Utara (Morut) hanya menerima khabar meninggalnya Bapak Bupati Aptripel Tumimor dengan rasa terharu yang dalam.
Fakta itu menunjukkan bahwa banyaknya Pemerintah Daerah yang jadi korban virus corona. Begitu pula Bupati Karawang yang masih di karantina menunggu proses masa inkubasi, dan Walikota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Bandung yang Alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh atau sudah ke luar dari fase isolas diri.
Fenomena lain dapat pula di lihat begitu banyaknya hal-hal yang berkorelasi dengan dimensi hukum, yaitu imbauan, surat edaran dan/atau maklumat. Silih berganti di keluarkan oleh Pemerintah Pusat, dan yang menjadi sasaran obyek himbauan adalah Pemerintah Daerah atau rakyat yang ada di daerah. Namun, patut disayangkan karena seringkali menimbulkan “kontradiktif” antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya, menjadi simpangsiur karena pejabat itu sendiri yang saling berbantahan. Dalam konteks ini, Presiden tidak hanya sebatas mengeluarkan imbauan, tetapi juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar tidak membuat kebijakan tanpa kordinasi dengan Pemerintah Pusat. Pernyataan ini member isyarat atau indikasi kuat bahwa Presiden tidak menghendaki kalau tidak mau mengatakan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 231
“menghindari” karantina wilayah. Terbukti dengan mengeluarkan keputusan; Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) .
Menindaklanjuti keputusan tersebut, sehingga berbagai instrument hukum (PP dan PERPU) telah di keluarkan, dan hal yang sama akan terus di keluarkan sebagai sebuah upaya antisipasi dari pemerintah selaku regulator. Bahkan tidak hanya itu, tetapi dana jaminan juga telah dikucurkan. Singkatnya, Presiden Jokowi tidak hanya sebatas menetapkan status darurat kesehatan dan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Akan tetapi, sebanyak Rp 406,1 triliun dikucurkan untuk penanganan wabah serta member stimulus ekonomi.
Hari-hari ini, harus diakui merupakan kondisi terburuk sepanjang sejarah bagi seluruh Pemerintah Dadaerah. Bahkan, mengalami posisi yang serba salah dalam menyikapi kedaan yang ada. Karena itu, menghadapi ancaman penyakit yang menakutkan ini, maka masing-masing daerah melakukan upaya penyelamatan masing-masing di daerahnya dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Bahkan, dengan melalui pendekatan-semangat kearifan lokal (kesetiakawanan) dan atau prinsif gotong royong.
Memang, dalam situasi seperti sekarang Pemerintah Pusat harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cepat. Bersinergi dengan semua tingkatan dan jajaran pemerintah, serta bersinergi dengan masyarakat itu sendiri. Hal-hal krusial seperti ini, tentu menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Apalagi, damfak virus ini sangat berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Maka, dapat di-mengerti, jika ke depan tingkat kriminalitas bagi kehidupan masyarakat akan menjadi potensi ancaman keamanan. Pada titik inilah, azas “Salus Populi Suprema Lex Esto” menjadi relevan yang harus diterapkan oleh pemerintah, yakni keselamatn rakyat adalah hukum tertinggi
Berdasarkan hal-hal tersebut, tentu siatuasi akan menjadi rumit jika berbagai aneka stimulus ekonomi tidak menjadi “resep” yang ampuh untuk mengobati penyakit ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, sebagai turunan langsung dari Pandemi Covid-19 .Dengan menyoal berbagai dimensi hukum yang ada, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk “otonomi daerah”dan merupakan inti “pelayanan public”tidak mungkin bisa dilaksanakan, jika tidak dilakukan melalui asas dekonsentrasi . Dalam kaitan ini, pelaksanaan asas dekonsentrasi harus dijalankan bersama-sama dengan asas desentralisasi dan/atau sentralisasi dalam sistem pemerintahan.
232 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Pada titik inilah, Gubernur diberikan kekuasaan penuh untuk
menyelenggarakan pemerintahan sebagai “Representatif” Presiden. Semua perangkat pemerintahan di daerah tunduk kepada komando Gubernur. Kapasitas selaku Gubernur menjalankan dua fungsi utama sekaligus, yaitu “tugas-tugas pemerintahan umum” dan “tugas-tugas pembinaan dan pengendalian otonomi daerah kabupaten/kota” sehingga akan sangat meringankan beban dari pemerintah pusat yang terlalu luas. Dalam posisi ini, Gubernur mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi sangat kuat. Gubernur berwenang mengawasi dan mengenda-likan jalannya penyelenggaraan otonomi daerah di daerah kabupaten dalam wilayahnya. Bahkan, berwenang menentukan derajat situasi dan kondisi sosial dalam lingkup wilayahnya.
Dengan bertolak pada asumsi dasar tersebut, maka sepatutnya pemerintah pusat member “keleluasaan” pemerintah daerah untuk menentukan pilihan-pilihan opsi yang akan diambil sebagai wujud pencegahan wabah Covid-19. Bukan sebaliknya pemerintah pusat justru “memantik” in-konsistensi dalam memutuskan berbagai kebijakan. Hal itu bisa di lihat, ketika pemerintah pusat memutuskan; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetapi di sisi lain, kebijakan pemerintahjuga diperbolehkan atau diberi kelonggaran mudik sepanjang yang bersangkutan jika tiba di tempat tujuan {lokasi daerah) langsung mengisolir diri secara mandiri. Tentu saja, sikap pemerintah pusat ini menimbulkan ketidakjelasan/ketidakpastian yang pada gilirannya ketidak konsistenan itu sendiri.
Ironisnya lagi, pemerintah memberikan kekuatan ekstrem kepada dirinya sendiri, tapi tidak mengambil tindakan ekstrem untuk memerangi wabah virus corona. Lagi-lagi hal itu bisa di lihat, tatkala Tenaga Kerja Asing (TKA) masih berdatangan dari luar, sementara kebijakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul (berkerumun). Dan, lebih tragis lagi, ketika muncul gagasan yang mengusulkan memberikan remisi pembebasan kepada napi koruptor dengan alasan virus corona. Sampai pengetikan tulisan ini masih pada level wacana (usulan).
Para aktifis dan kelompok masyarakat anti korupsi melakukan protes keras kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penolakan itu berisi agar Presiden Joko Widodo tidak mengabulkan/menolak permohonan usulan tersebut. Sebagai masya-rakat, dalam mencermati kehidupan bernegara yang tidak memberikan pemihakan yang jelas kepada rakyat tentu sangat disayangkan. Sebab
New Normal, Kajian Multidisiplin | 233
pada hakekatnya rakyat selalu mengingingkan roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang benar (on the track).
Oleh karena itu, jangan karena alasan pandemic virus corona, sehingga pemerintah menggunakan kekuasaan secara berlebihan atau melakukan tindakan yang dianggap melampaui kekuasaan yang di benarkan oleh Undang-undang. Seperti seruan sekelompok pakar yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, mengeluarkan peringatan keras bahwa tindakan darurat terkait dengan pandemi corona tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk tujuan politik. Sebab sejatinya, keberadaan pemerintah daerah (pemda) sebenarnya tidak lain dari membantu pemerintah pusat memberikan pelayanan public. Itulah sesungguhnya hakekat relasi pusat dan daerah dalam konteks tata kelola pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka menggerakkan birokrasi sebagai pelayanan publik yang baik di daerah. Maka, baik Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)memasukkan pengaturan terkait pelayanan public. Pemda diberikan kewenangan untuk menye-derhanakan jenis dan prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan/atau mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan ini, secara eksplisit bisa di lihat pada Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah-an yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Di samping itu, pemda harus pula memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat dan menuangkan informasi pelayanan ke dalam bentuk maklumat pelayanan public (citizen charter). Dalam operasionalnya, mereka dipimpin kepala daerah dibantu birokrasi, yaitu perangkat daerah, selevel dinas, badan, dan sekertaris daerah (Sekda). Itulah gambaran yang terjadi potret pemerintahan kita akhir-akhir ini, di tengah pandemi virus corona, pemerintah daerah dituntut bergerak cerdas-cepat dalam menerjemahkan berbagai kebijakan-kebijakan pusat. Dimana kesemuanya membutuhkan langkah-langkah taktis dan pergerakan dengan akselerasi tinggi. Meskipun beragam instruksi yang di keluarkan
234 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pemerintah pusat, akan tetapi nampak menimbulkan masalah-masalah kontradiktif/dilematis bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya.
Dalam kategori ini, contoh konkrit maklumat Kapolri untuk masyarakat agar tetap tinggal di rumah. Atau instruksi Mendagri kepada pemda untuk menghimbau warganya agar tidak mudik guna mencegah penyebaran corona. Tetapi di sisi lain, pemerintah mengizinkan mobil angkutan umum beroperasi untuk mengangkut penumpang yang akan mudik kedaerah masing-masing. Akhirnya gelombang arus mudik sulit “dibendung”, sehingga pemda diberi kerja tambahan lagi menyiapkan posko mudik/poskamling untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Instruksi lain, Presiden telah melakukan imbauan dan mengingatkan Kepala Daerah agar tak membuat kebijakan karantina atau apapun namanya tanpa kordinasi dengan pusat.
Himbauan tersebut nampak banyak yang tidak sejalan dengan realitas yang ada, sebab tetap saja ada birokrasi di daerah mengambil kebijakan lain. Artinya, sebagai wujud respon dari perubahan yang ada di masyarakat, sehingga otomatis perbedaan menjadi sebuah keniscayaan dengan pemerintah pusat. Realitas yang berbentuk keputusan yang berbeda ini bukan berarti mengingkari relasi pusat-daerah atau tidak melakukan kordinasi. Sebab komitmen pemerintah daerah yang ada digarda terdepan untuk melakukan penyelamatan cepat kepada rakyat, menjadi motivasi dan latarbelakang pengambilan keputusan.
Hal ini sejalan apa yang disampaikan Emile Durkhem; bahwa kebijakan harus seiring dengan perubahan masyarakat yang menjadi unsur perkembangan manusia. Durkhem menilai sebuah kekuatan yang ada dalam masyarakat merupakan bentuk kekuatan yang memiliki pola yang tidak statis akan tetapi dinamis yang selalu mengikutsertakan perkembangan dalam memenuhi unsur kebutuhannya. Karena itu, kebutuhan penyelamatan jiwa rakyat haruslah menjadi pertimbangan utama. Mengingat kasus wabah covid 19 sebarannya semakin massif, di laporkan per-hari ini (Senin 6/4/2020) sudah menyentuh angka lebih 2000 an yang berstatus positif. Itulah sebabnya, rasa kecemasan sudah samapi pada kehidupan lapis terbawah. Kini, sudah ada beberapa desa yang menyatakan melakukan isolasi diri, demi menjaga skala penyebaran virus ini yang bahayanya lebih menakutkan dari pada terorisme.
Walaupun, jauh-jauh hari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan ancaman global yang berpotensi lebih buruk ketimbang terorisme. Karena itu, dunia harus bangkit dan menganggap virus ini
New Normal, Kajian Multidisiplin | 235
sebagai musuh public nomor satu. Oleh sebab itulah, untuk memerangi Pandemi Covid-19 ini, sudah saatnya pemerintah pusat membangun relasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah. Bahkan sinergitas dengan rakyat, yaitu bersatu padu melawan corona. Dengan demikian, tentu saja dibutuhkan arah kebijakan yang lebih terarah, terkordinasi, dan konsisten. Dan, sekali lagi; sesuatu yang tak berguna atau tidak memberikan efek positif terhadap kemajuan bangsa haruslah dikesam-pingkan. Karena itu, berhentilah berdebat terhadap hal-hal yang hanya bersifat “politis” atau urusan personal yang konteknya hanya pencitraan.
Namun seyogyanya, dituntut kerja keras untuk merespon apa yang di tunggu oleh masyarakat sebagai suatu langkah yang tepat, seperti mengeluarkan aturan (regulasi) tentu kita berharap agar aturan itu secara normatif memang bisa diberlakukan secra efektif dan bermanfaat untuk meminimalisir atau meredam laju pertumbuhan virus corona. Katakanlah dalam konteks dikeluarkannya Pergub DKI, kita berharap penerapan Pergub DKI No 33 Tahun 2020 Tentang PSBB (Jumat 10/4/2020). Sesungguhnya, cikal bakal pergub ini adalah turunan dari PP No 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9/2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam rangka percepatan penanganan virus corona (Permenkes PSBB).
Sejujurnya, kalau kita mencermati perjalanan PP yang di keluarkan per- 31 Maret 2020 lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Permenkes, memang harus diakui bahwa langkah pemerintah masih sangat birokratis. Seperti kritik keras yang dilontarkan oleh Anggota DPR Komisi LX Fraksi PAN. Pemerintah terkesan sangat lambat dan kehilangan momentum setiap kali mengeluarkan kebijakan” ujar Saleh Daulay
Kelambatan pelayanan atau respon birokrasi ini, menunjukkan betapa pemerintah tidak memiliki sensifitas atau sense of belongin terhadap ancaman kesehatan rakyat yang dari hari ke hari mengindi-kasikan trend yang mencemaskan. Pada titik inilah, diharapkan langkah cepat, solutif, dan kordinatif dari pemerintah. Realitasnya, harus pula diakui bahwa praktek birokrasi masih saja menunjukkkan watak aslinya yang berbelit-belit dalam prosedur/mekanisme penetapan status PSBB. Sepatutnya, dengan menetapkan kondisi darurat kesehatan, maka seharusnya pula dibarengi dan atau ditindaklanjuti dengan cara-cara darurat. Misalnya, pada tingkatan operasional kebijakan pemerintah seyogyanya “menerobos” kelambanan birokrasi yang ada.
236 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Jadi, yang dibutuhkan sekarang, bukan berapa banyak regulasi
yang di keluarkan pemerintah, tetapi seberapa efektif kemanfaatan aturan untuk memperlambat atau mencegah laju penyebaran penyakit virus corona. Seperti kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan berkali-kali kebijakan, bahkan sudah pada level berlebihan (booming regulasi). Hal itu bisa di lihat, ketika pemerintah menerbitkan 3 regulasi sekaligus. Perppu No 1/2020, PP No 21/2020, Kepres No 11/2020, dan berlanjut dengan di keluarkannya Permenkes No 9/2020. Namun, disayangkan karena implementasi PP 21/2020 substansinya hanya sebatas mengatur tentang PSBB dalam lingkup percepatan upaya pencegahan Covid-19. Jika di telaah lebih dalam sanagt berbeda dengan konten materi muatan UU Karantina Kesehatan (vide UU 6/20180.
Dalam kontek pelaksanaan PP dimaksud, sangat komprehensif ruang lingkupnya karantina (rumah, wilayah, dan rumah sakit) serta pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian, operasionalisasinya harus holistic dan total. Tidak boleh parsial seperti sekarang, sehingga berimplikasi munculnya berbagai asumsi bahwa pemerintah pusat “berkelit” dari tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup dasar orang yang berada di karantina wilayah (vide Pasal 55 (1).
Oleh karena itulah, legitimasi hukum PP PSBB memerlukan pengaturan tindak lanjut (pelaksanaan). Hal itu bisa di lihat dari serangkaian Pasal dalam PP PSBB tersebut, mulai dari ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Meneteri Kesehatan adalah pihak yang member legitimasi atau persetujuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar. Usulan tersebut dapat disampaikan pemerintah daerah dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Perce-patan Penanganan Virus Covid-19. Dengan demikian, sesungguhnya kita berharap berbagai dimensi hukum mampu merespon kebutuhan pemerintah daerah dan pada tingkat operasionalisasinya berjalan efektif. Dikatakan efektif karena aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut (Pergub) sangat mematuhinya, sehingga tatanan aturan yang ada diberlakukan secara efektif.
Belakangan ini, kita menyaksikan begitu banyak aturan yang di keluarkan bahkan ada yang menyebutnya “over regulation”. Karena itu, tak berlebihan kalau ada yang menyebutkan, saat ini adalah era pemerintahan (Presiden) yang paling banyak mengeluarkan regulasi. Tentu saja, pemerintah tak dapat “menghindari” ketika situasi serba darurat, sehingga banyak agenda pemerintahan bergeser atau berubah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 237
dari jadwal sebelumnya. Bagaimanapun, keselamatan manusia haruslah menjadi nomor satu. Seperti kata Cicero sorang senator pada zaman Romawi: bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, yang lebih penting dilakukan sekarang ini untuk menurunkan angka penularan ialah kampanye perubahan perilaku. Tak ada pilihan lain, kacuali disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga tidak boleh kendor dan menganggap bisa melakukan apa saja seperti masa sebelum pandemic Covid-19. Itulah sebabnya dalam kondisi seperti sekarang, tak boleh bosan mengingatkan kepada keluarga/teman bahwa kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik jangan keluar rumah. Kalau harus keluar rumah, harus menggunakan masker. Selalu menjaga jarak, terutama kepada orang yang tidak dikenal karena khawatir ada kelompok orang tanpa gejala. Yang tidak kalah pentingnya selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.
Tentu pertanyaannya untuk apa semua itu dilakukan? Untuk mencegah jangan sampai kita tertular Covid 19. Karena itu, pintar-pintarlah menjaga diri sebab belum ada obat (vaksin) untuk penyakit yang satu ini. Untuk itu, kita harus menggerahkan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Tujuannya, agar dapat membawa perubahan besar kepada bangsa ini. Disiplin diri dan disiplin kolektif yang terbangun dari pandemi Covid 19 akan menjadi modal bagi kita untuk meraih kemajuan. Sejalan dengan itu, jauh-jauh hari ilmuwan sosial Samuel L Huntington menuliskan, pembangunan kultur dari sebuah bangsa merupakan kunci kemajuan. Siapa yang mampu membangun disiplin, etos kerja, sikap menghargai waktu, maka pasti bisa menghasilkan produk. Bahkan produk itu direproduksi menjadi barang bernilai tambah tinggi. Korea Selatan merupakan contoh Negara yang mampu membangun disiplin. Atas dasar itulah, Covid-10 tidak boleh melupakan tugas utama untuk membangun manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan serta memiliki iman dan taqwa yang kuat. Upaya untuk menurunkan angka penyeberan tidak boleh membuat proses belajar-mengajar kepada anak didik terhenti. Tidak boleh Covid 19 sampai menimbulkan generasi yang hilang.
Ikhtiar konkrit itu sekarang dilakukan proses belajar-mengajar dengan sistem jarak jauh. Covid 19 memaksa kita untuk bisa memberikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. Para pendidik (guru) terhebat yang kita miliki bisa mengajar kepada lebih banyak murid sehingga mampu memberikan pemerataan kualitas pendidikan, Itulah
238 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pelajaran terpenting dari 4 (empat bulan) lebih wabah covid-19 bahwa ternyata tidak mudah juga melakukan pendidikan jarak jauh itu (PJJ). Ternyata fasilitas pendukung untuk prose situ tidak tersedia mencukupi. Kemajuan tehnologi informasi ternyata masih terlalu mahal bagi banyak anak didik kita.
Gambaran yang ada menyadarkan kita, setiap hari menyaksikan bagaimana anak-anak di banyak daerah harus bertandang ke rumah tetangganya. Lebih ironis lagi ada yang ke pinggir gunung secara bergerobol untuk mencari signal, bahkan di Kota Makassar melalui bantuan Babinsa melakukan pembelajaran jarak jauh di atas kubur dengan mencantolkan Wifi dari Kantor Babinsa. Jadi proses belajar-mengajar ini syaratnya harus memiliki paket kuota yang memadai untuk menggunakan data. Dengan demikian dapat disimpulkan, kemajuan tehnologi informasi tidak boleh hanya sekedar dipakai untuk gaya hidup, tetapi yang paling utama untuk pendidikan. Negara harus hadir untuk bersimpati dan peduli pada masalah ini, yaitu proses belajar-mengajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, karena soal ini berkaitan dengan masa depan anak bangsa.
Akhirnya, sesudah lima bulan lebih wabah Covid-19 melanda Indonesia, tantangan tetap tidak mudah khususnya pada pada pengakan hukum. Pemerintah daerah mengalami situasi dilematis karena terkadang harus bergerak cepat menegakkan aturan yang ada . Namun pada soal lain berhadapan dengan (benturan) dengan nilai-nilai HAM yang terkandung di dalamnya. Belum lagi berhadapan dengan rakyat yang terkapar karena soal ekonomi akibat dirumahkan perusahaannya (PHK). Itulah berbagai soal yang menjadi masalah actual dan kekinian yang dihadapi Rakyat dan Pemerintah Daerah sekarang ini.
Apalagi dengan munculnya berbagai cluster baru penularan Covid-19, sehingga memantik berbagai polemik dan perbedaan pendapat yang kita saksikan akhir-akhir ini di ruang publik. Dalam konteks inilah, perlunya menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, menghargai perbedaan dalam kerangka Persatuan Indonesia berarti menerima keunikan setiap kelompok dan merawat ruang hidup bersama. Pemenuhan hak-hak asasi dan sipil setiap warga Negara dibatasi oleh kewajibannya untuk memastikan hak-hak warga Negara lain tidak dilanggar.
Alhasil, sebelum mem-Pancasilakan masyarakat, penyelenggara pemerintahan harus terlebih dahul mem-Pancasila-kan dirinya sendiri. Pada titik inilah, perlu digarisbawahi pejabat daerah-pusat (aparatur
New Normal, Kajian Multidisiplin | 239
Negara) tidak selalu punya integritas dan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Terlebih dalam kindisi multi krisis seperti sekarang ini yang dilamai bangsa kita, termasuk dilingkungan penyelenggara Negara itu sendiri. Maka, tentu tak mengherankan jika momentum yang ada sekarang justru tokoh-tokoh panutan masyarakatlah yang pantas menanamkan nilai Pancasila kepada penyelenggara Negara. Karena itulah, kejadian-kejadian konkrit setiap saat terhampar atau mewujud secara nyata dihadapan kita, sehingga sebagai anak bangsa tentu saja dibutuhkan “ikhtiar konkrit” dengan cara menginstitusionalisasikan (melembagakan) nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.
Penutup
Internalisasi dan Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kata kunci dalam menghadapi berbagai hal-ikhwal kondisi bangsa kita sekarang. Karena itu, pelembagaan nilai-nilai Pancasila dianggap dianggap perlu bahkan sangat penting sebagai suatu pendekatan utama dalam merespon berbagai gejolak bangsa, termasuk menghadapi dan/atau “melawan” Virus Corona atau yang lazim juga disebut Covid-19 sebagai suatu penyakit yang sangat berbahaya yang kini kita hadapi sejak awal tahun 2020 sampai sekarang.
Persoalan terletak pada kesadaran kita untuk bersedia merubah pola prilaku. Kita harus memang terus berikhtiar sehingga bisa Mengen-dalikan penyebaran (pertumbuhan) Covid 19 dan menekan angka fatalitas. Oleh karena itu, bagaimana mendorong warga Negara untuk dapat mengembangkan perilaku hidup berdasarkan nilai dan konsep Pancasila.
Tantangan lain yang dapat disimpulkan, bagaimana stakeholder (pengambil kebijakan) yang mengelola atau yang mengoperasionalkan Negara, baik pada tataran Pemerintah Pusat- Daerah ada singkronisasi dan harmonisasi dalam banyak hal, khususnya pada level implementasi. Dalam artian, kebijakan-kebijakan yang ada memiliki muatan nilai kearifan, sehingga kesamaan persepsi Pemerintah Pusat-Daerah dan Penegakan HAM selalu selaras dan/atau saling melengkapi sebagai wujud untuk menguatkan titik temu.
Rujukan
[1]. Yudi Latif, Aliansi Kebangsaan, masterpiece mengenai Pancasila, 2019
240 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[2]. Yudi Latif, Wawasan Pancasila, sebuah “Negara paripurna”
cetakan pertama, 2020. [3]. Abustan, Pilsafat Hukum (Konsepsi & Implementasi), PT Raja
Grafindo Persada, Cetakan ke-1 Januari 2020, ISBN 978-623-231-0469
[4]. Politik Kesehatan Masyarakat di Indonesia, Jurnal gagasan Vol 1 No 1 Tahun 2016 .
[5]. Anita Lie, AManusia Pancasila, Kompas (opini) Senin, 27 Mei 2019,
[6]. Bagir Manan, Nilai-nilai Dasar Keindonesiaan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan ke-1 2019
[7]. Yudi Latif, Memanjurkan Pancasila, Artikel Kompas 31 Mei 2019, Halaman 6 Opini .
[8]. Shidarta, Hukum Progresif, di Tengah Perubahan Masyarakat, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Halaman 175, Cetakan 1, 2019 .
[9]. Suryopratomo, Perubahan Perilaku, Podium Media Indonesia, Halaman 16, Selasa 28 Juli 2020 . .
[10]. Bunga Rampai Ragam Gagasan, Budaya Luhur Vs Budaya Pragmatisme, Penerbit PT Penjuru Ilmu Sejati, Cetakan pertama, 2016 .
[11]. M.Dawam Raharjo, Pancasila Telah Dilupakan,, Halaman 28, Cetakan 1 2016, ISBN; 978-602-0967- 25-7 .
[12]. Mohammad Nasih, Pancasila: Common Platform, Penerbit Sinergi Persadatama Foundation, Jurnal Gagasan Volume 1 No 1 2016. .
.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 241
Bab 16
“Jogo Tonggo”: Suatu Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penangan Covid-19 Sebagai Wujud Rekayasa Hukum Lita Tyesta ALW19; Adissya Mega Cristia20
Pengantar
Sejak 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan penyakit baru bernama virus Corona di Wuhan. Dalam waktu singkat, virus Corona telah menyebar luas di China bahkan menyebar luas ke setiap belahan dunia. Jika penyebaran Covid-19 memang bisa dikatakan semakin meluas hingga juga menyebar ke seluruh Indonesia , maka tidak heran jika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global. [1] Hingga Februari 2020 Indonesia masih belum ada laporan kasus orang yang terinfeksi Corona. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan pertama dua kasus baru Covid- 19 di Indonesia yang terletak di Depok Kota, Jawa Barat. [2] Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularan dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lain seperti tetesan ketika batuk & bersin atau melalui virus benda yang terkontaminasi. Sehingga begitulah percepatan penyebaran Covid-19 kini telah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Penyebaran Covid-19 telah menyebabkan berbagai masalah di Indonesia. Selain masalah kesehatan, Covid-19 telah menyebabkan masalah ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan.
Covid-19 yang muncul di Indonesia pada pertengahan bulan Maret ternyata membuat semua warga Indonesia bahkan dunia dibuat terperangah. Virus itu begitu cepat berkembang dan begitu ganas menyerang manusia dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kondisi genting ini, maka banyak pihak khususnya pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk melakukan langkah-langkah penangani persoalan ini. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dengan
19 Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang 20 Adissya Mega Christia, Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang
242 | New Normal, Kajian Multidisiplin
melibatkan juga berbagai komponen masyarakat. Hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan baik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan otonomi daerah, pemerintah pusat pada akhirnya menyerahkan penanganan Covid-19 ini ke masing-masing Pemerintah Daerah karena masing-masing Pemerintah Daerah bisa jadi memiliki kebijakan yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing daerah. Karena terkait penangan Covid-19, hal yang sangat urgent adalah persoalan perilaku masyarakat, oleh karena itu untuk penanganan tentunya dibutuhkan suatu upaya yang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sudah menjadi suatu hal yang mendunia dan merupakan salah satu upaya yang dianggap cukup efektif dan efisien sebagai langkah pencegahan .
Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah kasus Covid-19 melampaui Sulawesi Selatan dan sempat bergabung dengan tiga provinsi teratas dengan kasus terbanyak. Perkembangan terbaru ini menunjukkan situasi yang rumit dalam perjuangan Indonesia melawan virus ini. Provinsi yang terkena wabah paling parah sejak awal terus berjuang hingga hari ini, sementara yang lain telah muncul sebagai hotspot baru. Ini juga memberikan pandangan yang suram bahwa wabah ini di Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Provinsi Jawa Tengah terus berjuang untuk mengendalikan wabah sejak kasus mulai meningkat pada pertengahan Juni. Korban meninggal dunia di Provinsi Jawa Tengah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 1 Juli 2020. [3]
Menurut Saratri Wilonoyudho, kasus Covid-19 bukan semata-mata hanya sekedar masalah kesehatan, namun sudah melampauinya, yakni bio-psiko-sosial-spriritual. Hal ini dapat dilihat bagaimana sulitnya membangun kedisiplinan pada masayarak untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan dengan beberapa aturan hukum sebab sangat terkait dengan persoalan sosial di satu sisi tetapi juga perlu ada hukum sebagai payung dalam bentuk-bentuk kebijakan, maka ada baiknya perlunya rekayasa hukum untuk menangani persoalan Covid-19 khusunya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. [4]
Membahas mengenai rekayasa hukum, maka teringat pendapat dari Roscoe Pound yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep Law as tool of social engineering. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 243
untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. [5] Pendapat Pound di atas berbeda dengan pendapat Mazhab Sejarah yang menyatakan bahwa, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakkan oleh kebiasaan. Pound sebagai penganut aliran Sociological Jurisprudence berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif. [6]
Sebagai rekayasa sosial, maka hukum yang disusun dimaksudkan mampu untuk merubah perilaku masyarakat. Oleh karena itulah dalam menyusun peraturan diharapkan mampu menggali potensi adanya hukum kebiasaan, adat istiadat, hukum adat sebagai instrumen untuk dapat menjadi sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya materi muatan yang tertuang dalam peraturan harus memperhatikan berbagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, nanti akan dikaji bagaimana hukum digunakan untuk mampu menyelesaikan persoalan Covid-19 di di wilayah Jawa Tengah dan bagaimna materi muatan yang disusun mampu untuk merubah perilaku masyarakat.
Pembahasan
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk diamati, termasuk hubungan wewenang, kelembagaan, keuangan dan pengawasan. Hubungan otonomi ditunjukkan melalui kemampuan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Meskipun implikasi regulasi dari Pemerintah Daerah adalah mungkin, masih harus mengacu pada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam arti otonomi dalam negara kesatuan berarti mengandung esensi kepedulian terhadap negara kesatuan. Tanpa persatuan, tidak ada otonomi. Otonomi berisi unsur pengawasan untuk mencegah kemungkinn penyalahgunaan kekuasan sehingga mekanisme kontrol dilakukan melalui pengawasan [7].
Dalam hal ini, hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan baik dalam kerangka Negara Kesatuan maupun Otonomi Daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, misalnya menyediakan baik fasilitas kesehatan yang berkualitas dan penjaga kesehatan melalui peraturan
244 | New Normal, Kajian Multidisiplin
untuk membuat m yang kuat dan jelas. Pemerintah pusat telah me-nyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya terhadap Pemerintah Daerah. beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat telah diberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang dokumen dokumen tertulis . Tujuannya, tentu saja, agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman tentang Covid-19. Mendasarkan adanya pendelegasian kewenangan dalam hal penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Provisi Jawa Tengah melakukan juga langkah-langkah kebijakan hukum dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut.
Jenis Kebijakan Hukum
Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari aspek hukum terkait penanganan Covid-19, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum berupa berbagai bentuk, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Surat Edaran. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Gubernu Jawa Tengah adalah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.
Bagan 1. Skema Satgas “Jogo Tonggo” Kebijakan Instrusksi Gubernur tersebut karena adanya kewe-
nangan yang diberikan kepada daerah oleh Pemerintah Pusat. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk melawan covid-19 secara bersama-sama bergotong royong
Kebijakan secara hukum
Instruksi Gubernur
Satgas “Jogo
Tonggo”
a. Berbasis masyarakat
b. Berdasarkan
Prinsip Gerakan
Bersama-sama melalui Gerakan Gotong Royong
1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Sosial dan Keamanan
4. Bidang Hiburan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 245
mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk “Satgas “Jogo Tonggo”. Instruksi Gubernur ini ditujukan kepada seluruk Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang berjumlah 35 yang pada prinsipnya di masing-masing Kabupaten/Kota diketuai Kepala Daerah sebagai penanggungjawab Satgas daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang memiliki pengalaman dengan virus baru ini dan oleh karena itu wajar jika pihak berwenang menjadi "bingung" saat menangani krisis kesehatan dan terkadang membuat kesalahan dalam kebijakan. Kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama wabah. Semangat Indonesia adalah gotong royong, jadi kita tidak bisa begitu saja mendelegasikan tugas tertentu kepada pemerintah pusat, atau pemerintah daerah tertentu saja. Ganjar Pranowo menyatakan, program gerakan masyarakat yang diberi nama “Jogo Tonggo” bertujuan agar masyarakat Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi untuk mengelola pangan dan keamanan dalam menanggapi pandemi. Krisis ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan oleh karena itu bantuan keuangan pemerintah tidak akan pernah mencukupi. [8]
Konsep gerakan “Jogo Tonggo” merupakan konsep percepatan penanganan pandemi Covid-19 berbasis komunitas. Jogo adalah frasa dalam bahasa Jawa yang berarti menjaga atau menjaga, dan tonggo berarti tetangga, artinya saling peduli dengan tetangga. Masyarakat Jawa Tengah juga didorong oleh keinginan menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat. Kebersamaan anggota masyarakat dalam menghadapi krisis sosial ekonomi dengan membentuk jaring sosial di masyarakat. Partisipasi, keterlibatan masyarakat melalui RT dan kelompok-kelompok komunitas lain seperti ibu dasa wisma menunjukkan kesadaran diri setiap warga negara untuk berpartisipasi terlibat dalam semua hal yang menyangkut diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. [9]
Materi muatan Instruksi tersebut adalah sangat jelas bagimana Gubenrnur dalam membuat kebijakan sangat dipengaruhi pada budaya lokal masyarakat Jawa Tengah dengan konsep “Jogo Tonggo”. Kebijakan “Jogo Tonggo” ini merupakan kebijakan percepatan Covid-19 berbasis komunitas di tingkat Rumah Warga (RW), karena warga merupakan garda terdepan terhadap Covid-19. Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab untuk menangani wabah Covid-19. Jadi, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan warga negara sehingga wabah ini cepat
246 | New Normal, Kajian Multidisiplin
teratasi. [10] Instruksi tersebut pada prinsipnya berisi beberapa hal yang meliputi: 1. Memastikan seluruh warga di untuk melakukan upaya percepatan
penanganan Covid-19 secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan kesehatan warga; kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga; agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga; kondisi perekonomian masyarakat; kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok; kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat,
2. Menginstruksikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua RW untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kondisi geografis setempat melalui pembentukan Satgas “Jogo Tonggo”,
3. Menjamin pelaksanaan diktum kedua, dengan mengacu kepada Pedoman Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas “Jogo Tonggo” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubemur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini; Pedoman Rentang Kendali Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas “Jogo Tonggo”, Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubemur Selaku Ketua Gugus 'I‘ugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini,
4. Melakukan supervisi secara bexjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubemur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah,
5. Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Couid-19 Di Provinsi JawaTengah ini dengan penuh tanggungjawab.
Diharapkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dilakukan secara berkesinambungan, serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dan dalam waktu yang panjang, maka diperlukan pengorganisasian yang efektif, rapi dan kuat. Oleh karena itu, pembentukan Satgas melawan Covid-19 berbasis masyarakat “Jogo Tonggo” menjadi penting untuk segera dilaksanakan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 247
Satgas “Jogo Tonggo” adalah Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Could-19 di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan Couid-19 tepat sasaran dan tepat guna. Satgas “Jogo Tonggo” bukan organisasi yang dibentuk dari nol, melainkan mengkosolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial seperti Karang taruna, Dasa Wisma,Posyandu, dan warga di tingkat RW serta lembaga dan organisasi diluar wilayah RW yang terkait melawan Covid-l9. Jelas bahwa konsep tentang Satgas “Jogo Tonggo” itu berbasis pada masyarakat.
Pertanyaan yang muncul mengapa konsep Satgas Joko Tonggo menjadi pilihan Gubernur? Mari coba memahami pilihan konsep “Jogo Tonggo” yang diambil sebagai langkah kebijakan di bidang hukum. Pemerintah dalam menuangkan kebijakan hukum sangat berpijak pada kondisi masyarakat setempat atau dapat dikatakan berbasis kearifan lokal. Dalam masyarakat Jawa karakter khas dalam menjalani kehidupan, cenderung sederhana. , Jika dilihat dari sektor pembangunan dan perkembangan wilayah, Jawa Tengah ada dasarnya tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia, namun gaya hidup sederhana masih kental di Jawa Tengah. [11]
Bagan 2. Satgas “Jogo Tonggo” Sebagai Ciri Khas Masyarakat
Ciri khas masyarakat Jawa
Dari provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan RW
Berbasis pada masyarakat yang telah terbentuk melalui kelompok-kelompok sosial seperti Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, Warga
Tingkat RW serta lembaga dan organisasi di luar wilayah RW
Bukan bentukan baru
248 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Masyarakat Jawa Tengah cukup care dengan lingkungan, tenggang
rasa dan kekeluargaan, masih sangat kuat, Mereka punya istilah : Guyub Rukun. Ini menjadi ciri khasnya masyarakat Jawa tengah, disamping itu jiwa gotong royongnya, masih menjadi kehidupan sosial termasuk bagaimana kentalnya hubungan kekerabatan. [11] “Jogo Tonggo” dalam konsep Gubernur menjiwai rasa solidaritas masyarakat khususnya di pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal . Orang desa di wilayah Jawa Tengah memang terbiasa berbagi, apakah makanan, gotong royong membangun rumah dan menkjaga lingkungan dengan siskamling secara simultan dan berkesinambungan. Spririt inilah yang diambil dan menjadi dasar pertimbangan Gubernur untuk membentuk Satgas “Jogo Tonggo” “ yang memang berbasis pada kekuatan utama Jawa tengah yaitu desa.
Oleh karena itu, konsep yang dituangkan dalam Instruksi tersebut juga mengacu pada basis terbawah tertapi terdepan, mulai dari kelompok terkecil masyarakat, yaitu Dasa Wisma. Dasa Wisma ini merupakan Program PKK yang melibatkan maksimal 10 (sepuluh) keluarga dan mereka akan berkegiatan apa saja untuk kerukunan baik dalam kehidupan sosial, keagamaan, peningktan ekonomi. Dari Dasa Wisma naik ke tingkat RT, kemudian RW sampai Kelurahan. Inilah rangkaian konsep Jogo Tongoo dari Instruksi Gubernur yang dimulai dari tingkat Provinsi. Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan sampai ke Dasa Wisma dan Karang Taruna. Hal yang menarik bahwa konsep “Jogo Tonggo” ini bukan baru dibentuk saat terjadinya wabah Covid-19, tetapi kelompok-kelompok tersebut sudah terbentuk dari dulu dan Satgas “Jogo Tonggo” terintegrasi dalam Program yang sudah ada. Sehingga lebih mudah jalan dan tidak lagi menyusun hal baru.
Inilah sebetulnya konsep rekayasa hukum berbasis sosial dimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa social, diharapkan dengan konsep “Jogo Tonggo” ini mampu merubah kedisiplinan masyarakat untuk taat pada prookol kesehatan dengan berbasis kerukunan warga, sehingga tidak terkesan adanya paksaan. Gerakan ini mencakup 2 (dua) hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa, sosialisasi, pendataan dan pemantauan warga. Selain itu juga jaring pengaman ekonomi, yang terdiri 2 (dua) hal. Pertama, memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Covid-19. Kedua, mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca wabah. Pada setiap Satgas “Jogo Tonggo”dipimpin Ketua RW, yang dibantu oleh para Ketua RT, Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi dan tim keamanan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 249
Ketua satgas melaporkan setap hari ke Kelurahan/Desa demikian pula kelurahan/desa melaporkan ke kecamatan sampai ke kota dan ke Provinsi secara berjenajng sehingga setiap saat dapat dipantau perkembnagan dan keadaan warga di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pembentukan Satgas “Jogo Tonggo” pada saat dilaksanakannya Instruksi Gubernut tersebut tidak mengalami kendala yang berarti.
Di sinilah hebatnya Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mampu memadukan dengan melakukan rekayasa social dengan membentuk Satgas “Jogo Tonggo” dan rekayasa hukum dengan menuangkan dalam bentuk Instrusksi Gubernur No. 1 Tahun 2020. Inilah sebetulnya konsep rekayasa hukum berbasis social dimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa social, diharapkan dengan konsep “Jogo Tonggo” ini mampu merubah kedisiplinan masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan dengan berbasis kerukunan warga, sehingga tidak terkesan adanya paksaan.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
Dalam perkembangan selanjutnya ternyata pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalaian Covid-19. Tujuan utama dikeluarkanya Instruksi Presiden dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan kebijakan hukum tersebut karena angka penderita positif Covid-19 bahkan yang meninggal tidak juga menurun, diduga salah satu penyebabnya adalah masih kurang disiplinya masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama berlang-sungnya kasus Covid-19 ini.
Pemerintah mengangap perlunya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 dikeluarkan tidak hanya mutlak mengeluarkan sanksi, tetapi juga ada langkah untuk memadukan kesepakatan dari bermacam elemen-elemen masyarakat, serta mengabsahkan pemerintah daerah dalam menentukan sanksi dan penindakan dengan menggunakan kearifan lokal. Disinilah Pemerintah Daerah dituntut untuk berskap lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan. Langkah-langkah yang diambil Pimpinan Daerah Jawa Tengah dengan mencoba terlebih dahulu melakukan kajian yang cukup komprehensif dengan waktu yang cepat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut. Salah satu cara yang
250 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dilakukan dengan kajian secara social dan hukum bagaimana supaya masyarakat memiliki kesadaran dan patuh serta tunduk pada anjuran Pemerintah untuk melaksanakan protokol keseh.tan dengan disertai survey.Berdsarkan survey yang dilakukan Tim Penanganan Covid-19 di Jateng tentang “Perilaku Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19”, sebanyak 74,9 % responden menganggap Covid-19 sebagai masalah besar dan ada 6,7% yang masih menganggap bukan masalah serta 14,4% menganggap hanya masalah kecil. Angka 25% yang tidak mengangap Covid-19 sebagai maslah besar adalah angka yang banyak, apalagi kija diperoleh dari 35 juta pendiuduk Jawa Tengah. Jangankan 25% , 10 (sepuluh) orang saja tidak perduli akan menyulitkan penangannya. [4]
Konsekuensi Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mentaati dan mengikuti serta mematuhi. Untuk itu memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri menyusun dan memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam dalam membentuk peraturan gubernur/ peraturan bupati/ wali kota. Adapun Peraturan Gubernur dimasudkan untuk memberi payung hukum di dalam Gubernur mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah provinsi.
Materi muatan yang disusun dalam Peraturan Gubernur sudah ditentukan dalam Instruksi Presiden diantaranya adalah masalah penegakan hukum dengan pemberian sanksi baik bagi perorangan maupun maupun kelompok masyarakat. Bagian ini lebih difokuskan pada persoalan bagaiamana hukum mampu untuk merekaya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di Era Adapsti baru dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Penegakan Hukum
Makna penegakan hukum banyak dibahas dikalangan para ahli hukum, tetapi dalam tulisan ini lebih mengacu pada pendapat Prof Satjipto Raharjo. Dalam Bukunya Ilmu Hukum Satjipto Rahadjo mengacu pada pendapat Friedman ada 3 unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu substasi, struktur dan budaya hukum. Substansi terkait dengan paraturan, struktur terkait dengan kelembagaan penegakan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 251
hukum dan budaya hukum termasuk di dalamnya perilaku dan sikap masyarakat. [6] Adapun unsur penting yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain : 1. Peraturan
Peraturan ini menjadi penting karena peraturan adalah substansi dalam konsep oleh Lawrence Friedman. Bagaiamana peraturan itu disusun sangat mempengaruhi penegakan hukumnya. Oleh karena itulah pertanyaan yang muncul, peraturan macam apa yang mampu dijalankan dan akhirnya dipatuhi oleh masyarakat? Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui bahwa fungsi hukum dalam konsep Roscoe Pound, sebagai social control dan social engineering.
Konsep Roscoe Pound melingkupi 3 (tiga) hal yaitu bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat, diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat serta danya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia. [12] Pound berpendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi mampu mengubah perilaku masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Pound kemudian dikembangkan dengan konsep hukum yang memandang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat di samping saran untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan pada tataran praktis menuntut adanya inisiasi dari pembuat undang-undang untuk melakukan penemuan hukum guna mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari rekayasa sosial yang terjadi di Indonesia. [13]
Penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial di Indonesia sesuai dengan hukum modern yaitu hukum tidak sekedar mencari kesalahan orang lain kemudian memberikan sanksi hukum, tetapi hukum modern sekarang tercipta untuk mendidik orang untuk mengubah yang diinginkan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi hukum saat ini sudah bergeser, yaitu lebih aktif melakukan perubahan yang diinginkan. Pembangunan yang menempati posisi prima di Indonesia mengharuskan hukum menjadi rujukan dan kerangka acuan. Artinya, hukum harus dapat mendukung upaya
252 | New Normal, Kajian Multidisiplin
yang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik lahir maupun batin. [13]
Sebagai rekayasa sosial, maka hukum yang disusun dimak-sudkan mampu untuk merubah perilaku masyarakat. Oleh karena itulah dalam menyusun peraturan diharapkan mampu menggali potensi adanya hukum kebiasaan, adat istiadat, hukum adat sebagai instrumen untuk dapat menjadi sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya materi muatan yang tertuang dalam peraturan harus memprhatikan berbagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk me-ngokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maka harus menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru atau dapat meng-arahkan masyarakat ke arah tertentu yang dianggap lebih baik dan sesuai dari sebelumnya. [14]
Instruksi Presiden juga mensyaratkan bahwa dalam daerah penyusunan peraturan kepala daerah harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal terkait juga pada adanya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk juga memperhatikan perilaku masyarakat. Jadi, menyusun peraturan tidak sekedar menurunkan aturan tingkat atas untuk didelegasikan atau menuangkan wewenang ke tingkat di bawahnya, namun faktor masyarakat yang merupakan kekhasan di daerah harus diperhatikan. Terkait dengn ketaatan masyarakat diharapkan partisipasi berbagai unsur masyarakat yang ada, utamanya kelompok masyarakat yang sangat berpengaruhi terkait dengan protokol kesehatan, seperti kalangan medis yang berbasisi agama, para tokoh-tokoh agama yang ada, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, penegak hukum, swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Unsur Penegak Hukum Unsur ini sangat berpengaruh, oleh karena itu dalam
Instrusksi Presiden disebutkan adanya kerjasama dengan TNI/Polri sangat diperlukan. Karena ini bnetknya Peraturan Gubernur, alangkah baiknya juga melibatkan unsur Satpol PP yang dalam tugas dan fungsinya memang melakukan penegakan Peraturan di daerah.Tentunya tugas yang diembankan kepada Satpol PP dapat dilakukan secara terus menerus sehingga efektivitasnya dapat terlihat.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 253
3. Unsur Sarana Prasarana/Fasilitas (Sarpras) Unsur ini juga memegang kunci dalam penegakan hukum,
substansi bagus mekanisme yang disusun bagus, sanksi ada, namun bila sarpras yang meiliputi personal (SDM) dan dukungan anggaran yang kurang memadai juga akan mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukumnya.
4. Unsur Kesadaran Masyarakat. Ketiga unsur di atas sudah baik, namun kalau timgkat
kesadaran masyarakat yang dibangun kurang baik akan pula mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Kesadaran hukum masyarakat muncul karena adanya kepatuhan . kepatuhan timbul sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. Oleh karena itulah pemahaman tentang pentingnya dipatuhinya protokol kesehatan sangatlah penting. Salah satunya untuk memberikan pemahaman secara terus menerus berkesinambungan dengan berbagai sarana komunikasi harus dibangun. Komunikasi yang dibangun dapat dilakukan dengan berjenjang mulai dari tingkat terendah dalam masyarakat. Pemanfaatan konsep yang telah dibangun dengan satgas “Jogo Tonggo” lebih digalakan dan dimodifikasi dengan konsep dari Instruksi Presiden tentang penggunaan sanksi.
Dalam menindaklanjuti Inpres Presiden No. 6 Tahun 2020 yang antara lain berisi penegakan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang menjadi dasar penegakan hukum dan meminta Satpol PP menyiapkan rencana atau program penegakan hukum secara serentak di wilayah Jawa Pergub yang disusun ini sebagai panduan yang bersifat umum.masing-masing daerah kabupaten/kota diminta untuk menyiapkan sanksinya masing-masing. Sanksi yang akan diterapkan berupa teguran, lisan, tertulis, pencabutan izin sementara untuk usaha atau denda bahkan sampai pada sanksi berupa kerja social seperti menyapu jalan ( semarang sudah mengtrapkan sanksi tersebut). Sementara konsep “Jogo Tonggo” tetap dilanjutkan dengan memodifikasi atau memperluas pelaksanaan di setiap satuan kerja, misalnya di tempat kerja dengan melahirkan “jogo teman kerja”, di dunia usaha dimunculkan konsep “jogo karyawan” , di dunia pendidikan, “jogo siswa“, di pasar dengan “jogo pasar”. Program “Jogo Tonggo” ini diharapkan mampu menyentuh psiko- sosial masyarakat karena asumsinya
254 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tetangga, teman kerja, teman sekolah, tetangga harus dicintai sebagai saudara terdekat. Fokus konsep yang dibangun dengan “Jogo Tonggo” adalah membentuk perilaku patuh di level individu/keluarga. Asumsinya jika di level individu patuh akan mudah unutk mengatur di area publik. [4] Fungsi hukum sebagai sarana perubahan perilaku sosial masyarakat untuk menuju pada masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan dan menjalani hidup bersih karena ini salah satu kunci terhindar dari paparan Covid-19.
Contoh Nyata Pelaksanaan “Jogo Tonggo”
Provinsi Jawa Tengah adalah rumah bagi lebih dari 30 (tiga puluh) juta orang, telah memilih pendekatan berbeda untuk menangani wabah Covid-19 daripada memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) seperti banyak wilayah lain di Indonesia. “Jogo Tonggo” menggerakkan komunitas di mana orang-orang berkolaborasi untuk memastikan orang-orang menjaga jarak secara fisik, mengelola persediaan makanan, dan membantu orang lain dalam menanggapi pandemi. Warga RW 5 Kelurahan Jomblang di Candisari, Semarang, termasuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang sudah melaksanakan “Jogo Tonggo” dalam beberapa bulan terakhir.
Lebih dari tiga perempat penduduk RW 5 bekerja di sektor informal, kebanyakan sebagai buruh harian dan pedagang kaki lima. Sejak pandemi virus Corona melanda provinsi itu, 393 dari 539 keluarga di RW 5 terkena dampak finansial. Untuk membantu keluarga-keluarga ini, para tetangga membangun taman hidroponik dan memulai lumbung pangan kolektif di kantor RW 5. Masyarakat secara teratur menerima benih selada, terong, dan lada setelah menyampaikan rencananya kepada badan pangan provinsi dan juga membudidayakan ikan lele. Warga juga memprakarsai program menggambar dan mewarnai untuk menghibur anak-anak mereka selama pandemi.
RW 5 tersebut hanyalah satu contoh bagaimana tetangga saling membantu dengan pendekatan Jogo Tonggo di Jawa Tengah, yang berfluktuasi antara provinsi yang paling parah kelima dan keempat bahkan ketiga. Ganjar Pranowo mengatakan, pemerintahannya tidak memiliki dana dan sumber daya yang cukup untuk memberlakukan tindakan PSBB dalam jangka waktu yang lama, dan karenanya telah memutuskan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput untuk beradaptasi dengan situasi saat ini. Namun, keraguan atas kemanjuran program Jogo Tonggo tetap ada karena jumlah kasus Covid-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 255
19 di Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat. Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan sebab hanya 30 persen dari jumlah desa di Provinsi Jawa Tengah yang secara aktif melaporkan kegiatan Jogo Tonggo. [15]
Penutup
Uraian tersebut di atas menghantarkan pada kesimpulan, bahwa dalam rangka untuk menenggulangi wabah Covid-19 yang sangat cepat persebarannya, diperlukan kebijakan hukum yang tidak kalah cepat pula dengan melakukan rekayasa hukum yang mendasarkan pada kehidupan sosial, maka yang menjadi pilihan Provinsi Jawa tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur yang di dalamnya membentuk Satgas “Jogo Tonggo”. Konsep ini berbasis pada kearifan lokal dan spririt gotong royong masyarakat di Jawa Tengah, sehingga dalam pelaksnaannya tidak mengalami gejolak yang berarti.
Ide yang dilakukan dengan melakukan kombinasi rekayasa social yang ditompang dengan hukum yang dalam mareti muatan mengarah pada rekayasa hukum dimana diharapkan dengan kebijakan hukum tersebut mampu untuk mengubah perilaku masyarakat untuk lebih taat pada protokol kesehatan, sehingga ke depan makin mampu untuk memimalisisr korban pademi Covid-19 ini. Sedangkan persoalan penegakan hukum terkait tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang belum secara menyeluruh, kebijakan hukum diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di sinilah hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam penangan Covid-19 khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Rujukan
[1] R. P. P. M. Hasibuan dan A. Ashari, “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Viros Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat,” SALAM; J. Sos. Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7, hal. 581–594, 2020.
[2] D. Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” J. Publicuho, vol. 3, no. 2, hal. 267–278, 2020.
[3] H. Andrianto, “Central Java Joins Top Three Coronavirus-Hit Provinces,” Jakarta Globe, 2020. [Daring]. Tersedia pada: https://jakartaglobe.id/news/central-java-joins-top-three-coronavirushit-provinces. [Diakses: 28-Agu-2020].
[4] S. Wilonoyudho, “Rekayasa Sosial Penanganan Covid-19,” Suara Merdeka, 2020. https://suaramerdeka.news/rekayasa-sosial-
256 | New Normal, Kajian Multidisiplin
penanganan-covid-19/. [Diakses: 27-Agu-2020].
[5] L. Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya, 1990.
[6] S. Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986. [7] R. Wadi, “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam
Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penananganan Covid-19,” SALAM; J. Sos. Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7, hal. 613–624, 2020.
[8] Ivany Atina Arbi, “Regional leaders call on everyone to play role in overcoming pandemic,” The Jakarta Post, 2020. [Daring]. https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/21/regional-leaders-call-on-everyone-to-play-role-in-overcoming-pandemic.html. [Diakses: 28-Agu-2020].
[9] E. Arditama dan P. Lestari, “Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah,” J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha, vol. 8, no. 2, hal. 157–167, 2020.
[10] K. Sulistiani dan Kaslam, “Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” VOX Popul., vol. 3, no. 1, hal. 31–43, 2020.
[11] D. Ariko, “Karakter Khas Orang Jawa Tengah, ‘Nrimo Ing Pandum,’” Jawa Tengah Garuda Citizen, 2019. https://jateng.garudacitizen.com/karakter-khas-orang-jawa-tengah/. [Diakses: 06-Agu-2020].
[12] N. Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” Palar | Pakuan Law Rev., vol. 3, no. 1, hal. 73–94, 2017.
[13] H. Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 2018, vol. 147, no. 1, hal. 118–120.
[14] Y. Kusumawati, “Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum,” Sangaji J. Pemikir. Syariah dan Huk., vol. 1, no. 2, hal. 129–141, 2017.
[15] S. Atika, “Neighbors look after one another to combat COVID-19 in Central Java,” The Jakarta Post, 2020. https://www.thejakartapost.com /news/2020/06/28/neighbors-look-after-one-another-to-combat-covid-19-in-central-java.html. [Diakses: 28-Agu-2020].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 257
Bab 17
Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19; Tinjauan Psikologi Hukum Sudjiwanati21
Pengantar
Informasi pertama adanya wabah virus corona-19 di mulai dari Wuhan negara China dan berlangsung cepat menular ke seluruh dunia, penularan yang sulit dikendalikan semakin cepat sampai menimbulkan penularan berbagai negara dengan jumlah yang besar menjadi suatu pandemi virus. Pada masa era pandemi virus corona-19 banyak sekali perubahan dalam tatanan aturan kehidupan terhadap masyarakat di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Ada banyak peraturan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan angka kejadian penyakit akibat pandemi Virus corona-19. Sebagai contoh salah satunya adalah adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan karantina pada pasien yang menderita penyakit karena virus corona-19. Banyak masya-rakat yang mentaati peraturan dari pemerintah, namun ada pula peraturan karantina dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan karantina secara sengaja maupun tidak sengaja karena kurangnya informasi atau kemungkinan karena kurangnya pengetahuan atau mungkin disebabkan faktor lain [1]–[3].
Suatu peraturan hukum yang sudah dibuat oleh sekelompok masyarakat dipandang sebagai nilai-nilai hukum dan dipandang sebagai subsistem dari kebudayaan masyarakat. Lahir dan berkembangnya suatu peraturan hukum adalah dari tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan suatu masyarakat tertentu, yang dipelihara dan diwariskan secara tidak tertulis dari generasi ke generasi sebagai tata kehidupan yang mengatur ketertiban kehidupan dalam suatu kehidupan di masyarakat [4], [5]. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh suatu kekuasaan, untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hukum dapat juga dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan untuk ditaati oleh anggota masyarakat suatu negara. Peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan sebagai hukum yang sudah dibuat oleh suatu kekuasaan tidak dapat dipisahkan
21 Dr. Sudjiwanati, Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang
258 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dari suatu kehidupan yang ada di dalam suatu wilayah yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakatnya [6].
Pelanggaran hukum sering dikaitkan dengan kejahatan, makna kejahatan adalah suatu nama atau label yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh sebab itu maka pelaku tindak kejahatan disebut sebagai penjahat. Pengertian kejahatan bersumber secara alami dan memiliki nilai-nilai yang sangat relatif seperti norma yang ada di masyarakat dan nilai-nilai itu bergantung pada orang yang memberikan penilaian. Oleh sebab itu pula apa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan bukan selalu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula, misalnya semua golongan dapat menerima bahwa suatu perbuatan tertentu adalah suatu kejahatan, maka berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat pada masyarakatnya [7], [8].
Tujuan dari kajian psikologi terhadap pelanggaran hukum terhadap karantina pada pasien covid-19 dengan tinjauan psikologi hukum, adalah agar masyarakat memiliki referensi tentang pemahaman bahwa tindakan terhadap paksaan perlakuan terhadap pasien covid tergolong sebagai pelanggaran hukum. Kemanfaatan lainnya adalah untuk dapat membantu mahasiswa psikologi dalam mempelajari psikologi hukum dan masyarakat, memberikan informasi referensi khususnya tinjauan psikologi hukum. Kebutuhan referensi ini terbukti dari kebutuhan yang sering dilakukan oleh para teoritikus dan peneliti-peneliti lain meminjam definisi-definisi yang telah ada sebelumnya, dapat membantu mahasiswa-mahasiswa atau bidang ilmu yang membu-tuhkan. Kemanfaatan lainnya secara khusus dalam kajian psikologi terhadap pelanggaran hukum adalah memiliki hubungan erat dengan kepribadian seseorang. Kepribadian bukan hanya dari orang lain yang mengamati dan bukan juga sesuatu yang ada hanya bila seseorang bereaksi terhadap seseorang, tetapi kepribadian mempunyai ekstensi yang nyata dan menyangkut segi-segi neural atau segi-segi fisiologis. Maka pengaruh tindakan pelanggaran hukum itu juga dapat dari latar belakang kepribadian seseorang dalam menyikapi masalah kehidupan utamanya dalam konteks pandemi virus corona-19 yang banyak meresahkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia.
Pada Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Kelima Bulan Juli 2020 dinyatakan bahwa kegiatan penemuan kasus dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 259
kasus suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat dan melakukan respon adekuat. Dalam melakukan penemuan kasus tidak terpisahkan dari upaya kewaspadaan dini. Upaya penemuan kasus di pintu masuk diantaranya kegiatan penemuan kasus di pintu masuk bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kasus melalui pintu masuk negara baik melalui pelabuhan udara/laut maupun daerah perbatasan (check point). Informasi tentang virus corona-19 yang diperoleh masyarakat dari sumber yang signifikan misalnya dari Kementian Kesehatan tidak dapat dipercaya kebenarannya, tetapi masyarakat mendapat asupan informasi sangat banyak yang diperoleh dari berbagai media [6], [9].
Informasi yang dari sumber yang kurang signifikan kebenaranya inilah yang menimbulkan berbagai multi tafsir dari diri kepribadian seseorang yang mereaksi secara spontan atau secara berpikir terlebih dahulu atau mungkin disebabkan karena keluarganya yang menderita virus corona-19 maka terjadi hambatan berpikir yang mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran hukum.
Pembahasan
Pelanggaran Hukum Masyarakat di Era Pandemi Virus Corona-19
Perubahan yang ada di masyarakat terkait dengan pandemi virus corona menjadi masalah hukum yang perlu mendapatkan tatanan baru dalam kehidupan yang selalu berubah di masyarakatan. Tatanan baru itu sudah diundangkan oleh penguasa, tetapi dalam pelaksana-annya sulit dapat berjalan sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Adanya penolakan masyarakat tertentu dan adanya penerimaan dari masyarakat yang lain pula. Sejalan dengan kaidah hukum yang mengiringi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat dapat menentukan perubahan hukum dan perubahan mengikuti perkem-bangan tempat dan waktu. Hukum merupakan hasil yang dibuat oleh masyarakat suatu negara melalui badan peradilan yang berwenang memaksakan dan menegakkannya. Pemberian kewenangan bagi negara untuk memaksakan penerapannya maka hilanglah sifat abstraknya menjadi hukum konkrit[4], [5], [10].
Oleh sebab itu diperlukan aturan sebagai payung hukum dalam menerapkan aturan terkait masalah psikologi hukum dan psikiatri forensik. Sesuai dengan pendapat Kamil dan Fauzan (2008), mengemuka-kan bahwa masyarakat menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan tata tertib yang mereka perlukan pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang
260 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap dan bertindak di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain itu terlindungi. Salah satu dari makna aturan yang terkait dengan masalah lainnya adalah tentang kaidah hukumnya. Terdapat di dalam literatur bahasa Arab, “Kaidah” merupa-kan kata tunggal dari kata jama “Kawa’id”. Kini kata kaidah itu telah diterapkan menjadi Bahasa Indonesia [11]. Kamil dan Fauzan (2008) dalam kajian ilmu hukum, kaidah memiliki pengertian sebagai berikut: a. Hukum yang bersifat umum meliputi sub-sub bagian yang ada di
dalamnya. b. Hukum yang bersifat menyeluruh yang menjadikan jalan
terciptanya masing-masing sub hukum yang ada di dalamnya. c. Hukum yang berlaku sebagian besar yang meliputi sebagian besar
bagian-bagian hukum di dalamnya [11] Pada saat terdapat wabah penyakit menular di Indonesia
dilakukan dengan dengan berbagai cara penanggulangan dan pence-gahan, namun begitu cepatnya angka penularan sehingga menambah banyak kasus yang meninggal dunia. Wabah yang meluas pada seluruh lapisan masyarakat dampak mobilisasi masyarakat dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka cepat pula penularan wabah virus corona-19, sampai sulit untuk ditanggulangi. Walaupun sudah terdapat undang-undang terhadap wabah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1984 tentang penyakit menular, dengan penularan yang sangat cepat melanda seluruh masyarakat, maka Indonesia masuk dalam kriteria pandemic [12], [13].
Dikatakan wabah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berdasarkan Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah
kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
2) Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
3) Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 261
4) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. [14], [15]
Sebenarnya sudah ada aturan dari pemerintah yang mengatur tentang penyakit menular, wabah dengan program karantina. Pada saat terdapat wabah penyakit menular untuk menekan kejadian penularan penyakit menular maka pemerintah membuat program karantina. Adanya aturan ini sebenarnya masyarakat telah di lindungi oleh peme-rintah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Pasal 2, Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. [14]
Tetapi ada beberapa masyarakat yang mengabaikan masalah tentang wabah yang begitu cepat sampai meluas di seluruh Indonesia. Undang-undang yang sudah di buat oleh pemerintah sepertinya diabai-kan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan hingga melakukan pelanggaran besar yang merugikan keluarganya sendiri dan orang lain. Pelanggaran yang paling berat adalah mengambil paksa pasien covid-19 yang sedang dirawat di Rumah Sakit hingga mengambil paksa jenazah pasien covid-19 yang sudah dilakukan protokol pemulasaraan jenazah pasien covid-19. Pengambilan paksa pasien yang sedang dirawat dan jenazah pasien covid-19 merupakan pelanggaran terhadap karantina wabah penyakit. Pelanggaran karantina yang dilakukan oleh individu, keluarga dan masyarakat tertentu, dan menggerakkan massa yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hokum [16], [17].
Aturan tentang Pelanggaran yang dapat digolongkan menjadi pelanggaran terhadap undang-undang karantina yang dikuatkan oleh adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagai berikut: Berdasarkan Ketentuan Pidana Pasal 14 sebagai berikut. 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
penanggulangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam
262 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. [15]
Hukum pidana berkaitan erat dengan pertimbangan pertang-gungjawaban pelaku terhadap perbuatannya antara lain: 1) Toerakenin-svatbaarheid artinya pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan-nya. Toerakeninsvatbaarheid bermakna suatu keadaan normal pada saat seseorang mampu: (a) Untuk memahami arti dan akibat perbuatannya (b) Untuk menentukan kemampuan seseorang terhadap perbuatannya (c) Untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan masya-rakat 2) Ada kesengajaan atau kealpaan 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan pertang-gungjawaban pada seseorang yang melanggar hukum karantina merupakan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap aturan yang diun-dangkan oleh pemerintah. Berbagai faktor yang menjadikan adanya perilaku ketidak patuhan yang mengindikasikan adanya pribadi ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang ada di masyarakat yang konsekuensinya dapat digolongkan pada pelanggaran hukum pidana. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat terjadi karena kebanyakan orang mengikuti perintah karena adanya konsekuensi yang jelas atas ketidaktaatan seperti diskors dari sekolah, dipecat dari pekerjaan atau ditahan. Mereka juga taat karena berharap untuk dapat mencapai kondisi tertentu, seperti mendapatkan pujian, dihormati dan disukai banyak orang [5].
Peneliti psikologi melakukan penelitian dari perilaku manusia mengarahkan perhatian pada faktor yang mungkin menyebabkan orang taat ketika sebaiknya tidak taat: a) Melempar tanggung jawab kepada pihak otoritas b) Terbiasa melakukan tugas tertentu, yang dianggap sebagai tugas rutin c) Ingin terlihat sopan d) Terjebak [18]–[20]. Hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan sudah tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian pada berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut menitik-beratkan pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum dan aspek-aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Dasar-dasar kejiwaan dan pelanggaran terhadap kaidah hukum. 2) Dasar-dasar
New Normal, Kajian Multidisiplin | 263
kejiwaan dan pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum 3) Akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ruang lingkup Psikologi Hukum adalah sebagai berikut: 1) Tinjauan psikologi tentang terbentuknya suatu norma atau kaidah hukum 2) Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum 3) Perilaku-perilaku menyimpang 4) Aspek-aspek psikologi dalam pengawasan perilaku dan hukum pidana [20], [21].
Sejalan dengan perkembangan ilmu psikologi, juga terdapat perkembangan berbagai perilaku yang dapat ditelaah berdasarkan psikologi hukum antara lain yaitu adanya beberapa pelanggaran hukum terhadap karantina pasien covid-19 di masyarakat suatu negara. Pelanggaran karantina pasien covid-19 dapat terjadi dikarenakan faktor kelalaian atau belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap keterbatasan pengetahuan dan kurangnya informasi atau karena faktor kejiwaan tertentu. Pelanggaran hukum terhadap karantina pasien covid-19 akan merugikan masyarakat dengan penularan yang disebabkan oleh kontak dengan jenazah pasien. Oleh sebab itu diperlukan banyak informasi yang didapatkan seseorang agar dapat menurunkan angka pelanggaran hukum karantina pasien covid-19. Ilmu tentang psikologi hukum diperlukan oleh para psikolog dalam mengkaji beberapa kasus hukum murni dan atau kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 di masa pandemi menuju era new normal.
Tinjauan Psikologi Terhadap Pelanggaran Karantina Pasien Covid-19
Awal dari kajian ilmu psikologi adalah di mulai dari asal istilah psikologi, secara harfiah dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan atau scientific yang digunakan untuk menunjuk pada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah, yang meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat ilmiah. Kajian terhadap kasus yang melanggar hukum dalam kajian psikologi bertolak dari aspek-aspek psikologi dan psikodinamika yang ada pada diri seseorang, sampai terjadi perlaku yang dianggap melanggar hukum. Pengertian psikologi hokum adalah ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum [20].
264 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Perkembangan ilmu psikologi terus berkembang pesat
mengikuti perkembangan zaman, dan sudah banyak contoh yang ada di masyarakat bahwa, terapan psikologi telah digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang meminta layanan dan penggunaan jasa psikologi yang ada di dunia kerja dan dunia hokum [22]. Oleh sebab itu pendidikan psikologi di Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu lembaga yang mampu menempatkan the right man in the right place, mengingat dalam perkembangan dari masa ke masa banyak kejadian pada masyarakat ditemukan ada orang-orang yang kurang dan tidak kompeten menduduki posisi penting sehingga membuat keputusan yang salah untuk masyarakat dan negara. Oleh sebab itu psikologi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mulai diperlukan di ranah hukum. Pada awal perkembangannya, ruang lingkup psikologi adalah klinis yang berfokus pada abnormalitas atau penyimpangan yang terjadi pada manusia. pada perkembangannya, psikologi tidak dapat memfokuskan diri pada penyimpangan yang terjadi pada manusia, namun juga pada berbagai hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ataupun yang membuat manusia mampu berperilaku dengan cara tertentu, serta interaksi manusia dengan manusia lain ataupun objek lain [23].
Penanganan pemeriksaan masalah kejiwaan dalam kasus kriminal dilakukan oleh psikiater dan psikolog. Psikiater secara umum dapat menangani pemeriksaan kasus-kasus forensik, namun saat ini juga terdapat psikiater konsultan forensik yang khusus menangani kasus-kasus psikiatri forensik. Begitu juga para psikolog, tidak semua psikolog yang dapat melaksanakan pemeriksaan pada kasus hukum, tetapi sudah ada bidang psikologi yaitu bidang psikologi klinis. Seseorang yang membantu orang lain untuk menghadapi masalahnya dengan menerap-kan ilmu psikologi dan mempunyai gelar yang berhubungan dengan psikologi di bidang klinis disebut psikolog klinis. Tugas psikolog secara umum dalam rehabilitasi mental adalah: 1) Assessment: adalah proses evaluasi intelektual dan kepribadian seseorang dengan menitikberatkan pada penekanan implikasi aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari dan potensi vokasional yang dimiliki seseorang. 2) Intervensi dan Konsultasi: mencakup berbagai macam tritmen termasuk konseling atau psikoterapi individual dan kelompok, dukungan psikologi, pengurangan stress dan kecemasan terhadap masalah yang dihadapi [21], [23], [24].
Sedangkan kompetensi psikolog klinis adalah tergolong kompetensi profesi dalam penatalaksanaan kecemasan sesuai dengan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 265
bidang ilmu psikologi untuk mengatasi kecemasan adalah profesi yang menekuni ilmu kejiwaan adalah bidang ilmu Psikologi Klinis. Pelaksa-naan kompetensi menggunakan Standar kompetensi psikolog klinis yang disusun berdsarkan pada landasan Perundangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, dan Kurikulum Pendidikan Psikologi Klinis, dan Kode Etik Profesi serta berbagai referensi. Keilmuan dalam Psikologi secara khusus mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku unrtuk individu dan keluarga, kelompok dan komunitas. Secara luas ditujukan untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional dan perilaku. Mengintegrasikan ilmu psikologi dalam prevensi, asesmen, diagnosis dan tritmen pada persoalan manusia yang luas dan kompleks. Ruang lingkupnya meliputi sepanjang usia perkembangan, dalam kelompok yang beragam (kultur, etnis, sosio-ekonomi) dan sistem yang bervariasi, pelatihan, pendidikan dan supervisi berdasarkan pada hasil penelitian [14], [22].
Landasan ilmiah ilmu psikologi klinis adalah mempelajari dan menerapkan konsep dan teori Psikologi secara umum dan psikologi klinis secara khusus, dan mempelajari, menerapkan ilmu psikologi dan ilmu kesehatan yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan jiwa secara holistik dan komprehensif. Psikolog klinis berperan dalam melaksanakan tata laksana dan masalah gangguan psikologis sesuai dengan Diagnostic and Statistical Manual (DSM V dan DSM IV TR), antara lain adalah tentang spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya, gangguan afektif bipolar dan yang terkait dengan gangguan depresi, gangguan kepriba-dian, dan gangguan kecemasan, obsesif kompulsif dan gangguan terkait, gangguan terkait dengan trauma dan stres dan gangguan disosiatif [25]. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis. Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikolog klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas maupun tunuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi, dalam bentuk: a. psikoedukasi, b.konseling, c. psikoterapi, dan d. rekomendasi intervensi.
Aturan hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam ilmu psikologi dan kasus kejiwaan adalah aturan hukum yang berhubungan dengan berbagai kasus yang dibuat oleh kekuasaan antara lain adalah peraturan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis merupakan
266 | New Normal, Kajian Multidisiplin
peraturan hukum yang terkait dengan kasus kejiwaan dalam ranah kajian psikologi hukum. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah psikologi hukum dan yang terkait dengan psikiatri forensik dimulai pada salah satu perkembangan perundang-undangan di Inggris tahun 1843 yang dikenal sebagai hukum tidak tertulis yang disebut Humanitarian Decision. Termuat didalam aturan adalah bahwa apabila “seseorang dalam keadaan kacau akalnya dinyatakan tidak bersalah dan berhak dibebaskan”. Perkembangan hukum berikutnya adalah adanya hukum yang tertulis pertama yang pada tahun 1843 disebut The Mc. Naughten Rules. The Mc. Naughten Rules merupakan suatu usaha pembuktian sewaktu kejadian terdakwa dengan kasus kejiwaan. Termuat didalamnya adalah “kekurangan alasan karena gangguan ingatan/akal dengan cara melakukan right-wrong test”.
Berdasarkan undang-undang yang tidak tertulis dan undang-undang yang telah tertulis, seiring dengan perkembangan zaman, maka dalam penanganan kasus hukum yang berhubungan dengan kejiwaan sebenarnya sudah tersedia dan telah tertuang juga di dalam hukum pidana. Sejalan pula dengan penanganan dalam proses usaha menerap-kan prinsip kajian teori psikologi yang dilakukan ilmuwan psikologi maupun praktisi psikologi adalah untuk memecahkan sebuah masalah, yang seringkali berujung pada terciptanya sebuah teknik psikologi. Sebuah teknik psikologi yang berisi prinsip kajian teori psikologi tentunya dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi. Perkembangan ilmu psikologi bukan hanya pada teknologi informasi saja tetapi mulai berkembang terbukti bahwa telah banyak kasus yang membutuhkan penanganan melalui ilmu psikologi antara lain adalah kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan pelanggaran hukum lainnya dan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 [5], [20], [22].
Psikologi merupakan hasil studi tentang hakekat manusia, yaitu suatu ilmu yang menguraikan masalah kemauan serta motif dalam hubungan dengan peranannya dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Sebagai ilmu yang mempelajari respon tingkah laku terhadap stimulus dari lingkungannya, selaras dengan perkembangan zaman tentang kemajuan kehidupan masyarakat yang sealu berubah-ubah, maka juga terdapat adanya berbagai jenis perilaku yang bermacam-macam. Macam-macam jenis perilaku dari berbagai isu-isu kehidupan yang berubah-ubah, termasuk pada era pandemi virus corona-19 ini yang menimbulkan segala dampak yang buruk adalah banyaknya pelanggar-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 267
an hukum dan yang baik adalah memanfaatkan era perubahan menjadi suatu kreativitas yang menguntungkan untuk masyarakat luas.
Gambaran terjadinya pelanggaran yang terjadi di lapangan secara umum apabila ditinjau dari sudut pandang pskologis seseorang melalui ciri kepribadian, bahwa masing-masing individu memiliki ciri kepribadian yang relatif menetap, contohnya adalah seseorang yang pendiam, pemalu tetapi ada orang lain yang mudah mengungkapkan perasaannya, ramah., ada yang kekanak-kanakkan, kurang matang. Kondisi kepribadian seseorang berbeda dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, demikian pula apabila seseorang menghadapi masalah pada era pandemi virus corona -19. Perbedaan dalam menyikapi permasalahan keluarga yang menderita penyakit menular, mendapat informasi tentang penyakit yang simpang siur, masalah kebutuhan ekonomi dari dampak keluarga yang sakit, merupakan stimulasi dari perubahan kehidupan [21], [26], [27].
Stimulasi perubahan pada kehidupan seseorang dan sekelom-pok masyarakat menimbulkan respon yang berbeda pula, ada yang merespon merenung sejenak ada pula yang reaktif langsung bertindak. Kehidupan yang ada di dunia memang sudah banyak masalah yang dihadapi oleh orang yang normal tetapi juga dialami oleh juga oleh orang yang cacat fisik dan yang rentan terhadap gangguan jiwa dan yang ada kecenderungan melakukan pelanggaran hukum. Orang-orang yang rentan contohnya adalah cacat fisik yang dialami oleh beberapa orang, menderita penyakit menular, megalami penyakit yang kronis menahun. Masalah yang sedikit demi sedikit akan menumpuk dan menyebabkan rapuhnya kejiwaan seseorang yang terwujud dalam bentuk perilaku.
Kebanyakan seseorang yang merasa mengalami penderitaan dan masalah kekurangan terhadap dirinya sering menyalahkan bahkan mengutuk dirinya sendiri karena kecacatannya, dan kebanyakan menya-makannya dengan ketidakberuntungan dalam hidupnya. Orang-orang tergolong yang mengalami tingkat penyalahan diri dari perasaan bersalah sampai depresi, suatu depresi yang berbeda dengan duka cita bagi kehilangan sebagian dari dirinya. Pada orang dewasa yang disabilitas menyebabkan terbatasnya fungsi fisik atau penampilan fisik yang berbeda dengan orang lain, akan menyebabkan merasa berbeda dan terpisah dari orang lain. Perasaan terbelenggunya dengan masaah kehidupan yang seolah dirasakan sendiri oleh yang bersangkutan menimbulkan perilaku dan tindakan secara spontan dan tanpa terkendali. Permasalahan kehidupan yang kompleks ditambah dengan
268 | New Normal, Kajian Multidisiplin
permasalahan pandemi covid-19 akan dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan pelanggaran hukum yang perlu dikaji dari tinjauan secara psikologis [21].
Pada era akhir tahun 2019 ini kehidupan berubah drastis dari berbagai sisi kehidupan mulai diri pereorangan, keluarga, kekerabatan, peguyuban, kelompok agama dan masyarakat, sampai suatu negara. Perubahan suatu negara dalam berbagai sistem dan policy menimbulkan perubahan pada negara lainnya, demikian pula perubahan di tinjau dari sisi psikologis secara otomatis juga akan terjadi perubahan pada masyarakat suatu bangsa. Secara psikologis apabila seseorang meman-dang image mengenai dirinya untuk menjadi lebih tergantung pada orang lain, maka ukuran yang dipakai untuk melindungi dan mempertahankan konsep dirinya akan mereaksi bekerja sebagai bentuk melindungi diri dari pengaruh kecemasan. Hekekatnya pengambilan keputusan untuk menjadi ketergantungan diri pada orang lain yang dipaksakan juga akan dapat membuat seseorang dapat memuaskan kebutuhannya yang tidak terpuaskan pula [3].
Mempelajari berbagai macam tingkah laku manusia akan dapat mengenal seseorang dari perilakunya yang baik dan yang buruk yang ciri kepribadiannya terbuka dan ciri kepribadiannya yang tertutup. Ciri-ciri kepribadian masing-masing individu menampilkan berbagai macam perilaku stimulus dan respon terhadap individu yag lainnya [27].
Peraturan hukum yang dapat mengatur masalah kejiwaan, psikologi, maupun psikiatri sebenarnya sudah pernah diatur oleh peraturan dan undang-undang tidak tertulis. Oleh sebab itu apabila ditinjau ulang sebenarnya sudah ada peraturan hukum yang tidak tertulis dan adanya peraturan hukum yang tertulis yang mengatur orang-orang yang sakit kejiwaan. Sedangkan yang terkait dengan nilai-nilai hukum dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan biasanya dihormati dan dihargai secara kolektif oleh masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya, Tetapi nilai-nilai hukum selama belum masuk dalam rumusan kodifikasi hukum, maka dianggap tidak mempunyai daya normatif yang dapat dipaksakan penerapannya dalam masyarakat. Demikian juga apabila nilai-nilai hukum akan diterapkan pada kasus yang terkait dengan kasus psikologi hukum dan psikiatri forensik.
Perilaku-perilaku seseorang dapat menstimulasi perilaku orang lain yang akan mereaksi perilaku orang lain dengan reaksi yang baik, buruk, tindakan kriminal, penganiayaan, penipuan, penghinaan, pelecehan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, korupsi dan jenis
New Normal, Kajian Multidisiplin | 269
pelanggaran hukum yang lainnya yang dilakukan oleh orang yang normal dan yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu tingkah laku yang dapat dilihat oleh orang lain. Sejalan dengan perkembangan kemajuan zaman maka produk hukum akan menjadi kebutuhan untuk mengatur isu-isu dalam kehidupan, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengatur permasalahan perilaku orang yang melanggar hukum.
Masyarakat di era pandemi menuju new normal dan peraturan perudang-undangan yang diberlakukan dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu di dunia ini, antara lain adalah kajian dalam tinjauan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental dalam kehidupan seseorang sebagai individu atau manusia. Berbagai definisi psikologi yang dikemukakan oleh para ahli di bidang psikologi yang memiliki pengertian yang hampir sama. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju maka ruang lingkup psikologi juga berkembang termasuk ruang lingkup penelitian-nya pada seluruh masalah kehidupan. Masalah kehidupan antara lain tentang tumbuh kembang anak, masalah disabilitas dan penanganannya, masalah perkawinan, perceraian di masa pandemi, kekerasan dalam rumah tangga, cyber crime, kesulitan belajar anak di masa pandemi, kesulitan biaya sekolah, kekurangan dukungan internet di rumah, tidak terjangkaunya sinyal dari tempat tinggal, penularan penyakit covid 19, biaya pemeriksaan terhadap covid 19, dan kehilangan orang yang dicintai dengan banyaknya data kematian yang tinggi, pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tidak patuh pada aparat dan pada gugus penanganan covid 19, melarikan diri saat ada pemeriksaan kesehatan, mengambil paksa penderita untuk dirawat di rumah, dan mengambil paksa jenazah pasien covid-19 untuk pemulasaan jenazah sesuai agamanya masing-masing sampai pada pelanggaran pemakaman pasien covid-19 untuk di paksakan dimakamkan di pemakaman umum [28]–[30].
Berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penye-lenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaru-ratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00n (seratus juta rupiah).” [31]
270 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Kegelisahan psikologis di masa pandemi covid bukan hanya
dirasakan oleh penderita covid-19 saja tetapi melainkan juga dirasakan oleh keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, secara regional sampai wilayah propinsi. Terbukti dengan diberlakukan Work from Home, juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, walaupun masih ada beberapa karyawan yang memang harus melaksanakan pekerjaan di bidang yang berhubungan dengan kelangsungan hidup secara mutlak, misalnya bidang pangan dan fasilitas bahan hidup mutlak.
Aspek stimulus dari lingkungan mendapat respon yang berbeda dari berbagai individu dalam menangkap berita atau informasi dari berbagai media utamanya informasi tentang pendemi corona-19. Stimulus dan respon yang berbeda terhadap sturan pemerintah juga dipahami berbeda pula ada yang kurang paham adaa yang acuh ada yang memahami dan patuh terhadap aturan pemerintah yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya stimulus yang menimbulkan ketidakpahaman terhadap aturan menimbulkan kegelisahan psikologis dari individu, dan energi psikis yang kuat dapat menularkan emosionalnya ke lingkungan terdekat yaitu keluarga dan masyarakat sekitarnya. Motivasi dalam dalam bertindak berbeda antara orang yang satu dengan lainnya demikian pula apabila masyarakat sudah berkumpul akan berubah motivasi dalam tingkah lakunya, ada yang diam hanya mengamati, ada yang kondusif, ada yang melepaskan agresifitasnya dalam bentuk pelanggaran terhadap perlakuan pasien covid-19 [3], [32].
Energi psikis masyarakat dalam merespon stimulus lingkungan yang berada dalam satu kerumunan menjadi energi yang besar yang sulit dikendalikan, dinamika kepribadian individu menjadi berubah terpe-ngaruh dengan stimulus yang berubah pula. Perilaku yang berubah dipengaruhi oleh informasi adat kedekatan keluarga dalam menjunjung tinggi marabat keluarga, kekerabatan yang dalam, tradisi budaya dan keyakinan agama. Motivasi melakukan pelanggaran banyak di dukung oleh emosi, cinta, marah, benci, sedih, kecewa dan frustrasi dan kegelisahan klasikal, tindakan yang dilakukan dapat berbentuk spontan, dan atau oleh motivasi lain dan kemauan seseorang yang menjadi tujuan arah tindakannya.
Tinjauan psikologis dari teori Klages ada seseorang yang mudah tersinggung oleh suatu perangsang dan mudah bangkit dan alat perasa-annya tidak dalam letaknya. Sejalan dengan afek Klages membangi menjadi 3 sifat yaitu, aktif, pasif dan reaktif [21]. Pada tinjauan psikologi hukum adalah mengkaitkan masalah motivasi tindakan dan besarnya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 271
kemauan dan kuatnya niat yang telah direncanakan atau spontan pada saat melakukan pelanggaran hukum karantina pasien covid-19 baik di rumah sakit maupun di rumah dan di tempat pemakanan dan di lingkungan warga tertentu. Bentuk tindakan yang dilakukan tanpa disadari bahwa pengambilan keputusan dalam memperlakukan pasien covid-19 adalah merupakan tindakan kriminal berdasarkan undang-undang yang berlaku di negaranya.
Penutup
Kemauan seseorang di era perubahan memiliki bermacam-macam motivasi untuk memperoleh tujuan yang di inginkan, tetapi adakalanya tujuan yang dicapai bermanfaat bagi orang banyak tetapi ada juga yang merugikan banyak orang di sekitaranya. Kemauan yang reaktif bersifat keras kepala dan keras hati akan dapat menabrak aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemauan yang reaktif dengan indikasi keras kepala dan keras hati dalam mekanisme kerjasamanya merupakan kekuatan dua sifat yang saling berlawanan. Kekuatan kemauan terdiri dari daya kemampuan tetapi dalam bekerjasanya apakah sifat kemauan memiliki daya hambatan. Apabila seseorang kurang memiliki daya hambatan maka perilaku yang di lakukan adalah sangat mungkin menggunakan kekuatan kemauan tanpa dihambat sehingga melakukan pelanggaran hukum termasuk pelanggaran terhadap perlakuan pasien karantina covid-19.
Sedangkan orang-orang yang pasif hanya mengamati walaupun atas pertimbangan aspek keterdekatan dengan pasien, namun masih berpikir untuk mencari informasi yang belum dipahami. Namun dalam kondisi terlibat dalam kegelisahan masa maka seseorang dapat bergabung melakukan pelanggaran yang di sengaja maupun yang tanpa di sengaja dengan berbagai niat tertentu. Apapun tindakan dalam peris-tiwa pelanggaran hukum untuk diperlukan alasan niat melakukakan pelanggaran akan terbukti dalam kronologis di berita acara pemeriksaan demi hukum di Indonesia.
Berkaitan dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular terkadang juga banyak pelanggaran hukum baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Manusia pada dasarnya adalah baik adanya, masyarakatlah yang menimbulkan manusia berperilaku anti sosial untuk memperoleh kesem-patan dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum selalu berhubungan dengan manusia karena hukum diciptakan sesuai dengan kebutuhan tata tertib yang diperlukan pada suatu tempat dan waktu. Hukum dalam
272 | New Normal, Kajian Multidisiplin
suatu tempat dan tempat lainnya berbeda-beda. Oleh sebab itu hukum juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Setiap manusia pasti mengalami kekecewaan, konflik maupun kecemasan dan semuanya merupakan tekanan terhadap dirinya. Untuk mengatasinya manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri. Jika mekanisme pertahanan-nya tepat maka masalah yang dihadapi manusia akan dapat diatasi. Tetapi apabila kurang tepat menerapkannya, maka akan terbelenggu dalam berbagai masalah yang selanjutnya akan memunculkan gangguan kejiwaan dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Selain mekanisme pertahanan diri, yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran hukum adalah adanya interaksi sosial. Dalam hal ini interaksi sosial yang berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan seseorang dalam berperilaku.
Banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia memerlukan banyak para ahli, khususnya ahli psikologi. Karena menurut penjelasan diatas, permasalahan hukum berhubungan dengan permasalahan psikologis seseorang yang tidak terselesaikan. Tetapi para ahli tersebut mempunyai keterbatasan, bahwa mereka tidak dapat menjadi saksi ahli dalam suatu peradilan.
Peran dari hasil pemeriksaan psikologi pada suatu kasus adalah memberikan suatu makna dan interpretasi data yang berasal dari observasi, wawancara dan tes psikologi yang akan digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam suatu kasus atau perkara. Selain hasil pemeriksaan psikologi juga adanya hasil pemerik-saan psikiatri, dan yang penting dalam suatu perkara perlu adanya hasil pemeriksaan psikologi dan psikiatri sebagai tim saksi ahli untuk menunjang alat bukti. Kajian tentang hukuman dapat diputuskan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dalam suatu perkara. Selain keterangan ahli, alat bukti sah yang digunakan dapat berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, oleh sebab itu hasil pemeriksaan psikologi dan psikiatri berfungsi sebagai alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum penanganan wabah penyakit menular juga akan dilanjutkan proses hukumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban akan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Apabila proses awal sudah dilakukan maka sampailah pada tahap proses peradilan. Pada proses peradilan di Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia semestinya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 273
melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia pada kasus-kasus hukum dengan gangguan kejiwaan.
Kajian kasus-kasus hukum menunjukkan bahwa diperlukan adanya kerjasama yang erat antara ahli hukum dengan psikiater dan psikolog dengan membentuk forum komunikasi. Peningkatan kualitas mata kuliah di fakultas hukum dan di fakultas psikologi mata kuliah psikologi kriminal. Ahli hukum memberikan peluang masuknya saran-saran di bidang psikologi. Psikologi meningkatkan kualitas keilmuannya khususnya dalam bidang psikologi hukum. Banyak kasus pelanggaran hukum yang membutuhkan pemeriksaan psikologi, Hasil pemeriksaan psikologis yang ditemukan aspek psikologis yang cenderung memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum. Oleh sebab itu untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam perkuliahan memerlukan kurikulum psikologi hukum diperlukan beberapa mata kuliah antara lain psikologi forensik atau psikologi hukum atau psikologi kriminal, para psikolog, para ahli hukum diharapkan dapat menghadapi kasus-kasus psikologi yang erat terkait dengan masalah hukum.
Rujukan
[1] “Virus corona: Bagaimana China mengatasi wabah Covid-19 melalui teknologi tersembunyi, dengan penduduk dilacak lewat telepon genggam - BBC News Indonesia.” https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52141201 (accessed Aug. 20, 2020).
[2] H. P. Saputra, “Perubahan Sosial di Era Pandemi.” https://lombokpost.jawapos.com/opini/15/07/2020/perubahan-sosial-di-era-pandemi/ (accessed Aug. 20, 2020).
[3] I. M. Agung, “Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial,” PsikobuletinBuletin Ilm. Psikol., vol. 1, no. 2, pp. 68–84, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616/5058.
[4] A. Kamil and M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2008.
[5] S. Soenarto, KUHP&KUHAP. Jakarta: CV. Rajawali., 1991. [6] Moeljatno, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bina
Aksara, 1985. [7] L. Mulyadi, “Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-
Teori Kriminologi Dalam Perspektifilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern,” Jurnal Hukum PT Jambi. pp. 1–29, 2009, [Online]. Available:
274 | New Normal, Kajian Multidisiplin
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju7KOS-qfrAhUyIbcAHTAeCHcQFjAFegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpt-jambi.go.id%2Fuploads%2Fothers%2Fkajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teori_-_teori_kriminologi_da.
[8] N. Mubarok, Kriminologi Dalam Perspektif Islam. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
[9] Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
[10] P. J. Hairi, “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19,” Info Singk. Bid. Huk., vol. 12, no. April, pp. 1–6, 2020, [Online]. Available: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-%0A240.pdf%0A.
[11] A. Kamil and M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
[12] S. A. Poerana, “Ulasan lengkap : Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Tempat Ibadah,” 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e744bd328143/pencegahan-penyebaran-virus-corona-di-tempat-ibadah/ (accessed Aug. 20, 2020).
[13] S. Hegarty, “Virus corona: Kenapa wabah seperti ini semakin banyak di dunia?,” 2020. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51293615 (accessed Aug. 20, 2020).
[14] Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Konsensus Penatalaksanaan Gangguan Skizofrenia. Jakarta: PDSKJI, 2011.
[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Indonesia, 1984.
[16] D. Telaumbanua, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia,” QALAMUNA J. Pendidikan, Sos. dan Agama, vol. 12, no. 01, pp. 59–70, 2020, doi: 10.37680/qalamuna.v12i01.290.
[17] V. Turanjanin and D. Radulović, “Coronavirus (COVID-19) and possibilities for criminal law reaction in europe: A review,” Iran. J. Public Health, vol. 49, no. April, pp. 4–11, 2020, doi: 10.18502/ijph.v49is1.3664.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 275
[18] A. Bandura, “Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective,” Asian J. Soc. Psychol., vol. 2, no. 1, pp. 21–41, Apr. 1999, doi: 10.1111/1467-839X.00024.
[19] R. T. Schatz, E. Staub, and H. Lavine, “On the Varieties of National Attachment: Blind Versus Constructive Patriotism,” Polit. Psychol., vol. 20, no. 1, pp. 151–174, Mar. 1999, doi: 10.1111/0162-895X.00140.
[20] H. Akhdhiat, Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2011. [21] C. Wade and C. Tavris, Psikologi (Edisi Kesembilan). Jakarta:
Erlangga, 2007. [22] Sudjiwanati, Pencegahan Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Kode
Etik Psikologi. Malang: Unidha Press, 2015. [23] S. Slamet and S. Markam, Pengantar Psikologi Klinis. Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 2003. [24] N. M. T, D. A. Bernstein, and R. Milich, Introduction to clinical
psychology (4th edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hal., 1994.
[25] Sudjiwanati and N. Pnastikasari, Tata Laksana Kecemasan Remaja Dampak Informasi Wabah Virus Corona-19. Yogyakarta: Bildung, 2020.
[26] N. Khodijah, Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada., 2014.
[27] s Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
[28] Psikologi dan Teknologi Informasi. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia, 2016.
[29] R. Varalakshmi and R. Swetha, “Covid-19 lock down: People psychology due to law enforcement,” Asian J. Psychiatr., vol. 51, p. 102102, 2020, doi: 10.1016/j.ajp.2020.102102.
[30] Y. I. S. Setiawan, “Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19,” pp. 1–16, 2020, doi: 10.31219/osf.io/zfg6x.
[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Indonesia, 2018.
[32] P. Suppawittaya, P. Yiemphat, and P. Yasri, “Effects of Social Distancing , Self-Quarantine and Self-Isolation during the COVID-19 Pandemic on People ’ s Well -Being , and How to Cope with It,” Int. J. Sci. Healthc. Res., vol. 5, no. June, pp. 12–20, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 277
Bab 18
Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Lingkungan Keluarga di Era Pandemi Covid 19 Supriatnoko22
Pengantar
Bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Indonesia sudah memiliki nilai-nulai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup, jiwa, dan kepribadian dalam pergaulan. Nilai-niulai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia terdapat dalam adat istiadat, dalam budaya, dan dalam agama-agama atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Nilai-nilai luhur itu kemudian menjadi toloh ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi, seperti cita-cita yang ingin diwujudkannya dalam hidup manusia. Pandangan hidup yang terdiri atas rangkaian nilai-nilai luhur itu merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup atau weltanschauung berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi manusia dengan komunitas dan alam sekitarnya [1].
Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum menegara itulah kemudian oleh para pendiri bangsa digali kembali, ditemukan, dirumuskan, dan selanjutnya disepakati dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai dasar filsafat negara (filosofische grondslag) dari negara yang akan didirikan. Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia itu diformulasikan ke dalam nilai keimanan, nilai ketaqwaan, nilai keadilan, nilai keberadaban, nilai persatuan, nilai kesatuan, nilai mufakat, dan nilai kesejahteraan. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian kemudian disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka, oleh Ir. Soekarno diusulkan bernama Pancasila.
Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), rumusan nilai-nilai dasar negara tersebut diformulasikan Kembali
22 Dr. Supriatnoko, Politeknik Negeri Jakarta
278 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sebagai lima sila dengan urutan: (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasi-kan ke dunia sebagai sebuah negara merdeka. Merdeka dari penjajahan dan eksploitasi bangsa asing, menata kehidupan atas pemerintahan sendiri. Sehari setelah itu, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Sidang PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai pandangan hiudp bangsa dan pandangan hidup negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila lahir dari hasil perenungan jiwa yang mendalam, yang dilakukan oleh para pendiri negara (the founding fathers) [2].
Nah, dalam pengertian inilah, bangsa Indonesia yang hidup sekarang wajib memahami dan menghargai para pendiri bangsa beserta karyanya bahwa sebelum masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang menegara, nilai-nilai luhur Pancasila telah menjadi bagian dari kehi-dupan diri pribadi dan masyarakatnya. Setelah masyarakat Indonesia menjadi bangsa dalam Negara Kesatuan republik Indonesia, nilai-nilai luhur Pancasila itu dilembagakan sebagai pandangan hidup bangsa dan juga dilembagakan sebagai pandangan hidup negara. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan negara dimaksudkan untuk memungkinkan bangsa Indonesia dalam mengelola bangsa dan negara memiliki satu kesatuan sistem filsafat yang jelas dan sama—bangsa Indonesia memiliki satu pedoman dan sumber nilai sebagai hasil karya besar bangsa Indonesia—di dalam memecahkan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan serta hukum dalam gerak kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Pancasila bagi bangsa Indonesia seharusnya diperlakukan sebagai yang bersifat Kausa Finalis. Artinya bahwa Pancasila yang dirumuskan dan dibahas pada sidang-sidang BPUPKI dan panitia Sembilan serta ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai sebuah pandangan hidup bangsa dan negara yang sah dan di dalam menikmati kebebasannya di alam kemerdekaannya itu, seluruh bangsa Indonesia dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berkewajiban untuk memahami, mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman hidup
New Normal, Kajian Multidisiplin | 279
sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila yang bersifat Kausa Finalis itu bukan lagi sebagai pandangan hidup bangsa yang harus dipersoalkan dan diperdebatkan, tetapi secara berkesinambungan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia secara turun-temurun itu harus mampu diamalkan dan diimplementasikan oleh berbagai generasi sebagai sebuah identitas pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya saat ini dan kemudian selama negara dan bangsa Indonesia tetap eksis.
Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi dasar kajian pada bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan serta hukum. Jika semua bidang itu dikaji pada tulisan ini, tentu akan merupakan sebuah tulisan yang dapat dibuatkan sendiri sebagai sebuah kajian lengkap. Oleh karena itu, pada tulisan ini hanya akan diketengahkan pembahasan mengenai bidang sosial-budaya khususnya implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam lingkungan keluarga di Era Pandemik Covid 19 ini. Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam lingkungan keluarga menjadi menarik untuk diteliti, diobservasi, dan dituliskan hasilnya sebagai sebuah fakta pengamalannya oleh keluarga di era ini, mengingat peran penting orang tua dalam keluarga pada proses pendidikan di keluarga adalah “membentuk karakter” di samping dua peran penting lainnya, yaitu “mengajarkan keterampilan (skills)” dan “meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks)”. Nilai-nilai luhur Pancasila yang akan dibuktikan tentunya lebih dahulu diturunkan ke dalam nilai instrumental yang dapat kita temukan rinciannya dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) [3], dan dapat dilihat turunannya sebagai nilai praksis yang kita kenal dengan sebutan 18 Nilai Karakter budaya Bangsa [4].
Pembahasan
Nilai dasar: Prinsip dan Nilai Luhur Pancasila
Prinsip Pancasila dalam keseharian sering dikenal dan diucapkan sebagai Sila-sila dalam Pancasila. Prinsip dan nilai luhur Pancasila yang wajib dipahami sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan nilai dasar atau norma dasar yang berwujud abstrak umum universal, bersifat tidak berubah, tidak terikat dengan tempat dan waktu di seluruh wilayah Indinesia, menjadi identitas pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu: 1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
280 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Prinsip. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang pertama dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan acuan bahwa dalam pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada nilai yang terkandung didalamnya. Setiap pribadi bebas berpikir, bebas berusaha, tetapi sadar dan yakin bahwa akhirnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia rela dan ikhlas diatur. Kebebasan yang dimiliki setiap pribadi harus dipertanggungjawabkan dan harus menerima akibat dari pilihan tindakannya. Nilai Luhur: Nilai luhur yang terkandung dalam Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa adalah: a. Nilai Keimanan. Bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan keimanan bangsa Indonesia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur manusia dan seluruh alam semesta. Segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Nya dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.
b. Nilai Ketaqwaan. Bangsa Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan sikap berserah diri secara rela dan ikhlas kepada-Nya, bersedia tunduk dan patuh atas segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Nilai ketaqwaan yang membawa bangsa Indonesia mewujudkan kedamaian.
2. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Prinsip. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab merupakan prinsip yang kedua dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan acuan bahwa dalam olah pikir, rasa, dan tindak manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya-kewajiban asasinya secara adil dan beradab. Nilai Luhur. Nilai luhur yang terkandung dalam Prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dilandasi oleh Nilai Keimanan dan nilai ketaqwaan yang diwujudkan ke dalam Nilai Keadilan dan Nilai Keberadaban. a. Nilai Keadilan. Nilai keadilan ditandai dengan sikap menempatkan
pribadi dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajibannya serta harkat dan martabatnya diselaraskan dengan peran, fungsi dan kedudukannya. Nilai keadilan menciptakan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 281
kesetaraan dan suasana harmonis, tenteram dan damai karena setiap pribadi melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional.
b. Nilai Keberadaban. Nilai keberadaban menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut terminologi bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila diimplementasikan sebagai acuan pola pikir, sikap dan tindak dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Prinsip Persatuan Indonesia Prinsip. Prinsip Persatuan Indonesia merupakan prinsip yang ketiga dari Pancasila, memberikan acuan bahwa pola pikir, sikap, dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah kepada keutuhan dan kuatnya NKRI. Setiap pribadi dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia sehingga tercipta sikap bela dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal terjadi konflik kepentingan, tumbuh kesadaran untuk menempatkan kepentingan bangsa diletakkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. Nilai Luhur. Nilai luhur yang terkandung dalam Prinsip Persatuan Indonesia dilandasi oleh nilai keimanan dan nilai ketaqwaan, nilai keadilan dan keberadaban yang diwujudkan ke dalam Nilai Persatuan dan Nilai Kesatuan. a. Nilai Persatuan. Nilai persatuan merujuk kepada sikap masyarakat
majemuk bangsa Indonesia yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
b. Nilai Kesatuan. Nilai Kesatuan merujuk kepada keutuhan kesatuan wilayah dan negara Indonesia yang daratannya terdiri dari 17.508 pulau dengan batas wilayah negara berupa laut.
4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Prinsip. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan prinsip yang keempat dari Pancasila, memberikan amanat bahwa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, yang berdaulat adalah seluruh rakyat sehingga rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
282 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusuna kesepakatan bersama dengan cara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini hendaknya senantiasa diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Setiap keputusan hasil kesepakatan bersama mengikat semua pihak, tanpa kecuali, wajib melaksanakannya. Nilai Luhur. Nilai luhur yang terkandung dalam Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dilandasi oleh nilai keimanan dan nilai ketaqwaan, nilai keadilan dan keberadaban, nilai persatuan dan kesatuan yang diwujudkan ke dalam Nilai Mufakat. a. Nilai Mufakat. Nilai mufakat mencerminkan sikap terbuka untuk
menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama karena bersumber dari hati nurani dan bersendikan pada kebenaran hakiki, keadilan, keberadaban, dan keutamaan berupa kebijaksanaan.
5. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Prinsip. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan prinsip yang kelima dari Pancasila, memberikan acuan bagi olah pikir, sikap, dan tindak yang mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah. Nilai Luhur. Nilai luhur yang terkandung dalam Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilandasi oleh nilai keimanan dan nilai ketaqwaan, nilai keadilan dan keberadaban, nilai persatuan dan kesatuan serta nilai mufakat, diwujudkan ke dalam: a. Nilai Kesejahteraan. Nilai kesejahteraan mencerminkan terpenuhi-
nya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan batiniyah sehingga terwujud rasa puas, tenteram, damai, dan bahagia. Kondisi ini hanya dapat dicapai dengan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab [1], [5], [6].
Nilai Instrumental
Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai dasar yang abstrak umum universal berbentuk kaidah-kaidah pokok sejatinya belum dapat dioperasionalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat dioperasionalkan dalam kehidupan, nilai-nilai
New Normal, Kajian Multidisiplin | 283
luhur Pancasila harus diturunkan terlebih dahulu ke dalam nilai instrumental dan diwujudkan ke dalam nilai praksis.
Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila telah berusaha untuk menindaklanjuti kaidah-kaidah pokok sebagai nilai dasar ke dalam nilai instrumental [7]. Ketetapan MPR merupakan wujud dari nilai instrumental. Sayangnya, Tap MPR ini dicabut melalui Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 [8]. Meskipun Tap MPR No. II/MPR/1978 telah dicabut, menurut pendapat penulis, butir-butir pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila masih dapat digunakan sebagai nilai instrumental sepanjang belum ditetapkan nilai instrumental yang terbaru.
Butir-butir pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumus-kan dalam Tap MPR tersebut tersusun berdasarkan urutan Prinsip/Sila Pancasila, kemudian pada tulisan ini diposisikan sebagai nilai instru-menttal dan bersifat umum kolektif, dapat dihadirkan sebagai berikut. 1. Prinsip Ketuhanan Yang maha Esa
Bersumber pada nilai-nilai yang terkadung pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa: a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukuman hidup.
c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Prinsip Kemanusiaa yang Adil dan Beradab a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan
kewajiban antar sesama manusia. b. Saling mencintai sesama manusia. c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. g. Berani membela kebenaran dan keadilan. h. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.
284 | New Normal, Kajian Multidisiplin
3. Prinsip Persatuan Indonesia
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. c. Cinta tanah air dan bangsa. d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan betanah air Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang
ber-Bhinneka Tunggal Ika. 4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan a. Mengutamakan kepentingan negera dan masyarakat. b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama. d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan. e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah. f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur. g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
b. Bersikap adil. c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. d. Menghormati hak-hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. g. Tidak bersikap boros. h. Tidak bergaya hidup mewah. i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. j. Suka bekerja keras. k. Menghargai hasil karya orang lain.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 285
l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Nilai Praksis
Nilai praksis bersifat khusus kongkrit, wahana implementasi nilai dasar dan nilai instrumental secara nyata yang sesungguhnya. Nilai praksis sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa nilai dasar berfungsi dalam kehidupan sekaligus sebagai sarana mengevaluasi atas keber-hasilan atau kegagalan implementasi nilai dasar dalam sesuatu bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [1].
Pada tataran nilai-nilai luhur Pancasila yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan yang mudah diamati, diobservasi, dan dievaluasi, maka nilai dasar dan nilai instrumental diwujudkan ke dalam nilai praksis. Penulis memandang bahwa rumusan 18 Nilai Karakter dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional dapat dianggap sebagai rumusan nilai praksis.
Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 Nilai Karakter untuk mengantarkan kesadaran setiap individu bangsa/warga negara Indonesia sebagai pengamalan dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila [4], [9] sebagai berikut. 1. Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
286 | New Normal, Kajian Multidisiplin
6. Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 287
17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Implementasi Nilai-nilai Luhur Pancasila
Indonesia sebagai sebuah negara dalam semboyan “Bhinneka tunggal Ika” dibentuk dari berbagai etnis yang sudah ada di wilayah yang disebut “Nusantara” ditambah dengan datangnya “suku bangsa lain” yang menyatakan diri menjadi bangsa Indonesia, seperti yang datang dari negara-negara arab, negara-negara Asia lainnya, negara-negara Eropa. Mereka semua itu, yang telah menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia wajib menerima, mempelajari, menghayati, mengamalkan dan mengimplemen-tasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lingkungan keluarga merupakan kelompok terkecil dari kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di Era Pandemi Covid 19 ini dituntut untuk mengerti perbedaan antara “siswa belajar di rumah” dengan “siswa belajar dari rumah”.
Pada sebelum datangnya Pandemi Covid 19, orang tua dari setiap keluarga menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan pada sekolah melalui sarana luring dan siswa di rumah belajar mengingat dan mengulangi kembali pelajaran yang telah diterima dari guru di sekolah, itulah yang dimaksud dengan “siswa belajar di rumah”, sedangkan di Era Pandemi Covid 19 “siswa belajar dari rumah”, guru sekolah dan siswa melaksanakan proses pendidikan dari jarak jauh menggunakan sarana daring dan siswa menerimanya di rumah. Orang tua di rumah dilibatkan perannya dalam proses pendidikan ini. Pandemi Covid 19 selayaknya direnungkan secara sadar oleh setiap keluarga, pelibatan kembali keluarga dalam proses pendidikan merupakan bagian tugas dan kewajiban keluarga dalam memajukan pendidikan sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tugas dan kewajiban memajukan pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah kerjasama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Tugas dan kewajiban keluarga di era Pandemi Covid 19 ini adalah membantu guru sekolah dan pemerintah untuk membentuk karakter anak, mengajarkan
288 | New Normal, Kajian Multidisiplin
keterampilan, dan meningkatkan ipteks kepada anak yang menjadi siswa yang tercatat sebagai siswa di sebuah sekolah.
Pada tulisan ini, pembahasan diorientasikan khusus pada pemben-tukan karakter anak atau siswa sekolah. Keluarga yang dimaksud di sini adalah orang tua (ayah dan ibu), keluarga batih yang anaknya masih belajar di Sekolah Dasar. Pertimbangan sampel dari orang tua yang anaknya belajar di sekolah dasar, yaitu secara psikologis anak yang belajar di sekolah dasar belum dapat mengatasi permasalahan lebih mandiri dibanding dengan siswa yang belajar di sekolah menengah. Sampel secara acak adalah orang tua yang menjadi tetangga penulis di wilayah RT 03/RW 08 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor diberi angket isian tertutup mengenai nilai-nilai luhur Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk praksisnya, yaitu nilai karakter budaya bangsa yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, sekarang Kementerian Pendidikan Nasional berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulis menetapkan 11 dari 18 nilai karakter yang disurvey dan diobservasi. Nilai karakter tersebut yang penulis anggap sangat relevan dengan pelibatan keluarga pada proses pendidikan “siswa belajar dari rumah”, yaitu nilai karakter: religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, demokratis, bersahabat, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab, dan kreatif. Oleh sebab itu, responden yang diberi angket nilai karakter adalah orang tua dalam pelibatan proses pendidikan “siswa belajar dari rumah”. Orang tua menjadi figur sentral bagi anak melalui contoh-contoh pola pikir, pola sikap dan pola tindak atau perbuatan yang ditunjukkan orang tua kepada anak. Melalui analisis karakter yang disurvey dan diobservasi maka dapat ditarik kesimpulannya kepada prinsip dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai dasarnya.
Hasil Observasi dan Pembahasan
Nilai karakter yang diobservasi adalah nilai-nilai: religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, demokratis, bersahabat, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab, dan kreatif. Pengisi angket adalah para orang tua yang diwakili oleh keduanya atau satu di antaranya. Keluarga yang diobservasi sebanyak 20 keluarga tergolong keluarga menengah ke bawah di wilayah RT 03/RW 08 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Di samping diberi angket juga dilakukan wawancara. Pengisian angket dan dilaksanakan dari 1 Juli s.d 16 Agustus 2020. Disediakan 23 item pertanyaan dari 11 nilai karakter yang dijawab oleh setiap keluarga. Adapun hasil observasi dan pembahasannya diuraikan di bawah ini.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 289
Nilai Religius
Nilai karakter pertama yang disurvey dan diobservasi adalah nilai religius. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai religius, yaitu (1) Apakah Bapak/Ibu mengingatkan anak untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan agama yang dianut; (2) Apakah Bapak/Ibu meng-ingatkan anak dengan santun untuk melaksanakan ibadah. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (1), responden yang menjawab (Ya) sebesar 100%, yang menjawab (Kurang) 0%, yang menjawab (Tidak) 0%; pada item (2), responden yang menjawab (Ya) 55%, yang menjawab (Kurang) 45%, yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (1), responden menunjukkan bahwa responden mengingatkan anak untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhan-an Yang Maha Esa, sebagai Sila Yang Pertama dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (2), responden menunjukkan bahwa di dalam mengingatkan anak untuk melaksanakan ibadah dengan bahasa yang santun, sementara 45% menyampaikan dengan bahasa yang kurang santun seperti bernada marah. Walaupun demikian menyampaikannya dengan bahasa santun ataupun dengan bahasa yang kurang santun, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhan-an Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Jujur
Nilai karakter kedua yang disurvey dan diobservasi adalah nilai jujur. Pertama jujur dalam perkataan dan kedua jujur dalam tindakan atau perbuatan/pekerjaan. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai jujur, yaitu (3) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan; (4) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak untuk menjadi orang yang dipercaya dalam tindakan. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (3), responden yang menjawab (Ya) sebesar 90%, yang menjawab (Kurang) 20%, yang menjawab (Tidak) 0%; pada item (4), responden yang menjawab (Ya) 90%, yang menjawab (Kurang) 10%, yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (3), responden menunjukkan bahwa responden memperlihatkan contoh kepada anak untuk menjadi orang yang dipercaya dalam perkataan. Dengan demikian, responden mengim-plementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan
290 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Beradab sebagai Sila Kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (4), responden memperlihatkan contoh kepada anak untuk menjadi orang yang dipercaya dalam tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Toleran
Nilai karakter ketiga yang disurvey dan diobservasi adalah nilai toleran. Disediakan tiga item pertanyaan mengenai nilai toleran, yaitu (5) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama; (6) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan suku /etnis/budaya/warna kulit; (7) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak sikap untuk menghargai orang yang berbeda pendapat. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (5), responden yang menjawab (Ya) sebesar 100%, yang menjawab (Kurang) 0%, yang menjawab (Tidak) 0%; pada item (6), responden yang menjawab (Ya) 80%, yang menjawab (Kurang) 20%, yang menjawab (Tidak) 0%; pada item (7), responden menjawan (Ya) 40%; yang menjawab (Kurang) 60%; yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (5), responden memperlihatkan contoh kepada anak sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (6), responden memperlihatkan contoh kepada anak sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan suku/etnis/budaya/warna kulit. Dengan demi-kian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (7) responden memperlihatkan contoh kepada anak sikap kurang menghargai orang yang berbeda pendapat. Dengan demikian, responden kurang mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini dapat disebutkan bahwa responden kurang toleran terhadap orang yang berbeda pendapat karena pertimbangan lebih didasarkan pada sikap subjektif suasana hati dan terhadap orang yang dihadapinya.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 291
Nilai Disiplin
Nilai karakter keempat yang disurvey dan diobservasi adalah nilai disiplin. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai disiplin, yaitu (8) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh perbuatan tertib dan patuh pada ketentuan agama; (9) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh perbuatan tertib pada kehidupan sehari-hari. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (8), responden yang menjawab (Ya) sebesar 90%, yang menjawab (Kurang) 10%, yang menjawab (Tidak) 0%; pada item (9), responden yang menjawab (Ya) 40%, yang menjawab (Kurang) 60%, yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (8), responden memperlihatkan contoh perbuatan tertib dan patuh pada ketentuan agama. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan. Pada item (9), responden kurang memperlihatkan contoh perbuatan tertib pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, responden kurang mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa dan dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Kerja Keras
Nilai karakter kelima yang disurvey dan diobservasi adalah nilai kerja keras. Disediakan satu item pertanyaan mengenai nilai kerja keras, yaitu (10) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh kepada anak upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan menyelesai-kan tugas anak yang diterima dari sekolah. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (10), responden yang menjawab (Ya) sebesar 60%, yang menjawab (Kurang) 35%, yang menjawab (Tidak) 5%.
Pembahasan: pada item (10), responden memperlihatkan contoh kepada anak upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan menyelesaikan tugas anak yang diterima dari sekolah.
Nilai Demokratis
Nilai karakter keenam yang disurvey dan diobservasi adalah nilai demokratis. Disediakan tiga item pertanyaan mengenai nilai demokratis, yaitu (11) Apakah Bapak/Ibu menunjukkan contoh sikap dan tindakan kepada anak agar anak menjadi pribadi yang memiliki hak dan kewajiban
292 | New Normal, Kajian Multidisiplin
yang sama dalam kehidupan sosial; (12) Apakah Bapak/Ibu senang menerima dan menghargai jika anak memberi pendapat; (13) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh sikap kepada anak untuk menghormati orang lain. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (11), responden yang menjawab (Ya) sebesar 95%, yang menjawab (Kurang) 0%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (12), responden yang menjawab (Ya) 40%, yang menjawab (Kurang) 55%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (13), responden menjawab (Ya) 50%; yang menjawab (Kurang) 35%; yang menjawab (Tidak) 15%.
Pembahasan: pada item (11), responden menunjukkan contoh sikap dan tindakan kepada anak agar anak menjadi pribadi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanu-siaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (12), responden kurang senang menerima dan menghargai jika anak memberi pendapat. Dengan demikian, responden kurang mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (13) responden memperlihatkan contoh sikap kepada anak untuk menghormati orang lain. Dengan demikian, responden mengimplemen-tasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Bersahabat
Nilai karakter ketujuh yang disurvey dan diobservasi adalah nilai bersahabat. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai bersahabat, yaitu (14) Apakah Bapak/Ibu memperlihatkan kepada anak rasa senang berbicara dan bercanda dengan anak; (15) Apakah Bapak/Ibu memper-lihatkan kepada anak rasa senang bekerjasama dengan orang lain. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (14), responden yang menjawab (Ya) sebesar 90%, yang menjawab (Kurang) 10%, yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 293
menjawab (Tidak) 0%; pada item (15), responden yang menjawab (Ya) 90%, yang menjawab (Kurang) 10%, yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (14), responden memperlihatkan kepada anak rasa senang berbicara dan bercanda dengan anak. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Persatuan Indonesia dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Pada item (15), responden memperlihatkan kepada anak rasa senang bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Persatuan Indonesia dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Gemar Membaca
Nilai karakter kedelapan yang disurvey dan diobservasi adalah nilai gemar membaca. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai gemar membaca, yaitu (16) Apakah Bapak/Ibu menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang membangkitkan kebijakan bagi diri pribadi; (17) Apakah Bapak/Ibu menyediakan berbagai bahan bacaan untuk membangkitkan minat baca anak. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (16), responden yang menjawab (Ya) sebesar 20%, yang menjawab (Kurang) 55%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (17), responden yang menjawab (Ya) 30%, yang menjawab (Kurang) 45%, yang menjawab (Tidak) 25%.
Pembahasan: pada item (16), responden kurang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bahan bacaan yang membangkitkan kebijakan bagi diri pribadi. Dengan demikian, responden kurang mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (17), responden menyediakan berbgai bahan bacaan untuk membangkitkan minat baca anak. Dengan demikian, responden kurang mengimplemen-tasikan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Peduli Sosial
Nilai karakter kesembilan yang disurvey dan diobservasi adalah nilai peduli sosial. Disediakan dua item pertanyaan mengenai nilai peduli sosial, yaitu (18) Apakah Bapak/Ibu senang membantu anak dalam belajar agar anak mampu menyelesaikan tugas dari sekolah secara mandiri; (19)
294 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Apakah bapak/Ibu memperlihatkan kepada anak rasa senang untuk memberi bantuan kepada orang lain. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (18), responden yang menjawab (Ya) sebesar 95%, yang menjawab (Kurang) 0%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (19), responden yang menjawab (Ya) 75%, yang menjawab (Kurang) 20%, yang menjawab (Tidak) 5%.
Pembahasan: pada item (18), responden senang membantu anak dalam belajar agar anak mampu menyelesaikan tugas dari sekolah secara mandiri. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (19), responden memperlihatkan kepada anak rasa senang untuk memberi bantuan kepada orang lain. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Tanggung Jawab
Nilai karakter kesepuluh yang disurvey dan diobservasi adalah nilai tanggung jawab. Disediakan tiga item pertanyaan mengenai nilai tanggung jawab, yaitu (20) Apakah Bapak/Ibu memotivasi anak untuk bertanggung jawab terhadap yang diperbuatnya; (21) Apakah Bapak/Ibu memotivasi anak untuk ikut meringankan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan tingkat usianya; (22) Apakah Bapak/Ibu memotivasi anak untuk ikut menjaga kenyamanan hidup dengan tetangga. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (20), responden yang menjawab (Ya) sebesar 90%, yang menjawab (Kurang) 5%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (21), responden yang menjawab (Ya) 45%, yang menjawab (Kurang) 55%, yang menjawab (Tidak) 5%; pada item (22), responden menjawab (Ya) 95%; yang menjawab (Kurang) 0%; yang menjawab (Tidak) 5%.
Pembahasan: pada item (20), responden memotivasi anak untuk bertanggung jawab terhadap yang diperbuatnya. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai Persatuan Indonesia, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam
New Normal, Kajian Multidisiplin | 295
kehidupan sehari-hari. Pada item (21), responden kurang memotivasi anak untuk ikut meringankan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan tingkat usianya. Dengan demikian, responden kurang mengimplemen-tasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai Persatuan Indonesia, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada item (22) responden memotivasi anak untuk ikut menjaga kenyamanan hidup dengan tetangga. Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip dan nilai-nilai luhur Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip dan nilai-nilai Persatuan Indonesia, prinsip dan nilai-nilai luhur Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Kreatif
Nilai karakter kesebelas yang disurvey dan diobservasi adalah nilai kreatif. Disediakan satu item pertanyaan mengenai nilai kreatif, yaitu (23) Apakah Bapak/Ibu memberikan ide atau usul atau solusi untuk memberi kemudahan kepada anak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Hasil observasi diperoleh data sebagai berikut: pada item (23), responden yang menjawab (Ya) sebesar 65%, yang menjawab (Kurang) 35%, yang menjawab (Tidak) 0%.
Pembahasan: pada item (23), responden memberikan ide atau usul atau solusi untuk memberi kemudahan kepada anak dalam menyelesai-kan masalah-masalah yang dihadapinya Dengan demikian, responden mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai luhur Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Penutup
Prinsip dan nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat nilai dasar, untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari harus diwujudkan terlebih dahulu ke dalam nilai instrumen dan nilai praksisnya. Pada nilai praksis itulah nilai dasar Pancasila dapat dioperasionalkan, diamati, dan dievaluasi. Nilai praksis yang disurvey dan diobservasi sebanyak 11 nilai-nlai karakter budaya bangsa bersumber dari Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan
296 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Nasional. Seturut dengan itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 11 nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian yang diimplementasikan di lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian ditemukan nilai-nilai luhur yang kurang dalam implementasi di lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai toleran, nilai disiplin, nilai demokratis, nilai gemar membaca, nilai tanggung jawab. Temuan-temuan yang disimpulkan kurang dalam implementasi diuraikan sebagai berikut. Pada item (7) responden memperlihatkan contoh kepada anak sikap kurang menghargai orang yang berbeda pendapat. Dengan demikian, responden disimpulkan kurang toleran. Pada item (9), responden kurang memperlihatkan contoh perbuatan tertib pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, responden disimpulkan kurang disiplin. Pada item (12), responden kurang senang menerima dan menghargai jika anak memberi pendapat. Dengan demikian, responden disimpulkan kurang demokratis. Pada item (16), responden kurang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bahan bacaan yang membangkitkan kebijakan bagi diri pribadi. Dengan demikian, responden disimpulkan kurang gemar membaca. Pada item (17), responden kurang menyediakan berbagai bahan bacaan untuk membangkitkan minat baca anak. Dengan demikian, responden disimpulkan kurang gemar membaca. Pada item (21), responden kurang memotivasi anak untuk ikut meringankan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan tingkat usianya.
Dengan demikian, responden disimpulkan kurang menumbuhkan tanggung jawab. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa semua nilai-nilai luhur yang bersumber pada nilai dasar Pancasila dapat diimplementasikan oleh responden walaupun dalam tingkat implementasi yang berbeda, yaitu antara nilai-nilai luhur yang diimplementasikan dengan baik dan dengan kurang dalam implementasi. Temuan nilai-nilai luhur yang kurang dalam implementasi hanya dapat ditingkatkan menjadi baik atas dasar kesadaran diri pribadi orang tua dalam lingkungan keluarga masing-masing mengingat peran penting dari keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat di Era Pandemik Covid 19 dalam menyukseskan proses pendidikan “siswa belajar dari rumah”. Survey dan observasi yang dikerjakan untuk menghadirkan pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai luhur Pancasila pada tulisan ini merupakan langkah penelitian awal, sehingga terbuka untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan keluasan sampel wilayah dan responden yang lebih besar lagi. Wassalam.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 297
Rujukan
[1]. Supriatnoko, “Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Ajar untuk Perguruan Tinggi”. Penaku, Jakarta.2008.
[2]. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, “Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi”, Jakarta, 2016.
[3]. BP7 Pusat, “Bahan Penataran P4: Pancasila/P4”, BP-7 Pusat, Jakarta, 1996.
[4]. Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, “Nilai-nilai Karakter Berlandaskan Budaya Bangsa”, Jakarta, 2010.
[5]. LPPB (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara), “Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara”, Jakarta, 2005.
[6]. Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di era Globalisasi”, JPK: Jurnal Pansasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1 Januari 2017.
[7]. BP7 Pusat. “Bahan Penataran P-4: Pancasila/P-4”, Jakarta, 1996. [8]. Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Penyunting), “Restorasi
Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”, Brighten Institute, Bogor. 2006.
[9]. Zulfikar Putra, “Implementasi Pendidikan Pancasila sebagai Character Building Mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka”, Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 299
Bab 19
Polemik Keputusan Pemberhentian Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya Zainal Abidin Achmad23
Pengantar
Sejak bulan Februari 2020, Indonesia secara cepat menerapkan kebijakan untuk antisipasi perluasan sebaran COVID-19. Presiden Republik Indonesia (RI), Bapak Joko Widodo mengawali serangkaian kebijakan terkait COVID-19 ketika melangsungkan rapat terbatas kementerian luar negeri di Bandara Halim Perdanakusuma. Langkah pertama adalah membahas rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, lokasi pertama munculnya virus Corona. Termasuk membahas lokasi penampungan sementara para WNI dari Wuhan dengan penempatan lokasi observasi dan karantina di pulau Natuna. Kebijakan lain adalah penghentian jadwal penerbangan langsung dari dan ke daratan utama China, pelarangan bagi WNI untuk melakukan perjalanan ke daratan utama China, dan penghentian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrivals ke Indonesia, untuk sementara waktu, bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang bertempat tinggal di daratan utama China [1].
Setelah pemberlakukan kebijakan untuk urusan hubungan luar nageri, pemerintah RI menindaklanjutinya dengan penerapan berbagai kebijakan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk urusan di dalam negeri. Salah satunya adanya pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang secara rutin melaporkan perkembangan penyebaran COVID-19 dan penanganannya dari seluruh wilayah provinsi di Indonesia melalui siaran televisi nasional pada sore hari, sekaligus menghimbau agar warga Indonesia selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, mematuhi protocol kesehatan, di lingkungan rumah dan di tempat umum. Seluruh warga Indonesia dapar mengetahui terjadinya penambahan kasus corona yang terus bertambah dari hari ke hari, baik mereka yang berstatus Orang
23 Dr. Zainal Abidin Achmad, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya.
300 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) [2].
Dengan mengabaikan kontroversi pernyataan Menteri Kesehatan Terawan yang kontra produktif terhadap penanganan COVID-19, Pemerintah RI menunjukkan kesigapan dengan bertindak cepat untuk menangani setiap kemunculan kasus COVID-19, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sebagaimana dapat dilihat sejak awal Maret, ketika mulai diumumkannya ada warga yang mendapat status ODP. Pemerintah RI terus menghimbau untuk menjaga kesehatan dan melakukan hidup sehat, menghindari orang yang sedang sakit batuk, hingga mulai menggunakan masker saat pergi keluar rumah atau saat bertemu dengan orang. Tidak hanya itu dari segi kesehatan pemerintah juga menyedikan rumah sakit, alat kesehatan yang memadai untuk persiapan jika nantinya terdapat penambahan kasus. Peraturan pun juga terus dibuat dan diperbarui terutama mengenai jalannya keluar masuk di negara Indonesia, pihak imigrasi mulai melarang masuk warga negara asing hingga melakukan transit dari daerah yang dilarang seperti China, Italia, Iran, dan Korea [3].
Penerbitan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, menun-jukkan bahwa pemerintah tidak sekadar memperhatikan urusan luar negeri, imigrasi, dan kesehatan. Sebagaimana penerapan PSBB pertama kali di Jakarta pada tanggal 10 April 2020, menunjukkan pengaturan dalam urusan pekerjaan (WFH), perkantoran, dan kegiatan belajar mengajar dirumah [4]. Penerapan PSBB di Jakarta tersebut karena menjadi wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia hingga tanggal 19 Juni 2020. Tetapi secara signifikan, angka statistik di Jakarta menunjukkan adanya pelambatan kenaikan kasus. Sedangkan urutan kedua terbanyak kasus COVID-19 ada di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan statistik antara DKI Jakarta dengan Jawa Timur, adalah pada angka statistik di Jawa Timur yang masih menunjukkan kenaikan kasus dan belum menunjukkan adanya pelambatan.
Setelah pemberlakuan PSBB di Jakarta, segera disusul oleh pemberlakuan PSBB di kota-kota lain akibat bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Beberapa kota di Jawa Timur secara beruntun memberlakukan PSBB, bahkan Surabaya menjadi kota dengan jumlah kenaikan penderita COVID-19 paling tinggi di Indonesia. Berawal dari ditetapkannya 34 orang PDP berasal dari Kota Surabaya dari 65 kasus se-Jawa Timur per tanggal 5 Maret 2020 [5]. Bagi Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan episentrum penyebaran COVID-19. Sebagai
New Normal, Kajian Multidisiplin | 301
langkah antisipasi perluasan penyebaran, Gubernur Jawa Timur menilai perlu untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik (Surabaya Raya), terkait rencana pemberlakuan PSBB. Sebagaimana hasil koordinasi dan kesepakatan antara tiga pimpinan daerah tersebut dengan Gubernur Jawa Timur, maka secara resmi tiga daerah yang memiliki jumlah terbanyak kasus tersebut memberlakukan PSBB mulai tanggal 19 April 2020. Tercatat pada tanggal itu, jumlah kasus COVID-19 di Surabaya melonjak dengan 1806 orang dinyatakan ODP, yang berasal dari 31 kecamatan di Surabaya [6]
Gambar 1: Data Penyebaran COVID-19 di Indonesia Periode 19 Juni
2020 (Sumber: Indonesia Indicator) PSSB Surabaya Raya mengalami dua kali perpanjangan. Masa
pemberlakuan PSBB pertama, resmi berakhir tangga 11 Mei 2020. Perpanjangan pertama berlaku hingga tanggal 25 Mei 2020. Ternyata hingga batas akhir tanggal 25 Mei, jumlah kasus semakin banyak sehingga PSBB di Surabaya Raya diperpanjang lagi hingga tanggal 8 Juni 2020. Ketika akan melakukan perpanjangan ketiga, ternyata ketiga pimpinan daerah di Surabaya menolak melakukan perpanjangan PSBB. Padahal jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Surabaya hingga tanggal 7 Juni 2020, tercatat mencapai 3124 ODP dan menjadi daerah terbanyak penyebaran COVID-19 di Jawa Timur [7]. Harapan Gubernur Jawa Timur agar ketiga wilayah melakukan perpanjangan PSBB, tidak sejalan dengan
302 | New Normal, Kajian Multidisiplin
keputusan para pimpinan daerah di Surabaya. Hal inilah yang menjadi perdebatan publik di media massa dan media sosial.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai fasilitator, akhirnya secara resmi menyetujui dihentikannya pemberla-kuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 8 Juni 2020, oleh ketiga pimpinan daerah di Surabaya Raya. Sebuah keputusan yang tidak populer di tengah masih tingginya angka positif kasus COVID-19 di Surabaya Raya. Polemik pun muncul di tengah masyarakat karena terdapat perbedaan harapan antara Gubernur Jawa Timur dengan tiga pimpinan daerah di Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Perbedaan pendapat bermunculan di media massa, antara pejabat provinsi, walikota Surabaya, ahli pandemi, dan profesional medis. Data statistik resmi dari pemerintah provinsi Jawa Timur sebenarnya menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus COVID-19 belum selayaknya PSBB di Surabaya Raya dihentikan.
Pembahasan
Perkembangan COVID-19 merupakan bahan berita yang wajib diperoleh media massa. Para jurnalis berusaha mendapatkan dan menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19, kasus-kasus viral tentang penolakan pemakaman, penolakan keluarga pasien terhadap status PDP, penolakan penjemputan untuk isolasi, dan update terkini jumlah orang terinfeksi setiap harinya. Berbagai jenis media massa juga berebut menyampaikan perkembangan kasus COVID-19, baik Koran, Radio, Televisi, dan media daring. Tidak ketinggalan media sosial, seperti Line, Facebook, Youtube, Instagram, dan WhatsApp. Tetapi kecepatan penyampaian informasi menjadi alasan bagi seluruh media untuk memberikan kemudahan akses kepada khalayak. Koran, televisi dan radio juga telah turut bermediamorfosis dengan mengembangkan penyampaian informasi dengan platform internet [8]–[11]. Teknologi internet yang semakin maju sehingga mempermudah akses khalayak ke berbagai situs berita yang tersedia. Media daring adalah tatanan baru yang terus mengalami perkembangan [12]–[15]. Sehingga siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi di mana saja, melalui media apa saja, kapan saja, senyampang tersedia koneksi jaringan internet.
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap temuan hasil analisis berita dengan model framing Pan dan Kosicki dengan subjek berita dari detik.com, kompas.com, dan e100ss (radio suara Surabaya). Ketiga media tersebut adalah media daring yang memiliki pengaruh besar dalam
New Normal, Kajian Multidisiplin | 303
dalam mengangkat isu COVID-19 di Jawa Timur, khususnya PSBB di Surabaya Raya di media. Detik.com dan kompas.com adalah media coverage nasional yang sangat berpengaruh untuk isu COVID-19 di Jawa Timur (peringkat 1 dan 2 nasional), sedangkan e100ss merupakan media coverage lokal dan regional tetapi menjadi media lokal yang paling berpengaruh pada isu yang sama (peringkat 14 nasional, peringkat 1 lokal). Peringkat pengaruh ketiga media ini, diketahui dari penelusuran melalui akun Zainal Abidin Achmad melalui portal data analisis media sosial Drone Emprit Academic, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 [16].
Meskipun bukan portal media daring pertama di Indonesia, namun detik.com saat ini merupakan situs berita terpopuler di Indonesia, dengan keunggulan pada kecepatan unggahan berita-berita baru (breaking news). Detik.com hanya memiliki edisi daring dan tidak ada edisi cetak sejak awal lahir tanggal 9 Juli 1998. Kompas.com lahir pada tahun 1995, lebih awal daripada detik.com. Kompas.com tidak hanya membuat berita dalam bentuk teks tetapi juga berbentuk gambar, video, hinggal live streaming. Bersama detik.com, kompas.com menjadi portal berita daring yang paling diminati. Sedangkan e100ss ialah portal berita yang muncul pada tahun 1999, sebagai bagian dari Radio Suara Surabaya (radio SSFM) yang sudah ada sejak 11 Juni 1983. Radio SSFM adalah radio berita yang paling terkenal di kota Surabaya dan Jawa Timur.
Ketiga media tersebut memiliki perspektif sendiri dalam menyikapi fakta dihentikannya pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya. Pasti terjadi polemik akibat perbedaan cara pandang masing-masing media. Perbedaan perspektif mempengaruhi konstruksi fakta ke dalam penulisan berita. Terkadang sudut pandang penulisan banyak dipengaruhi oleh sudut pandang jurnalis pada saat melakukan peliputan dan penulisan. Sudut pandang seorang jurnalis tidak akan mampu merusak isi sebenarnya sebuah fakta, tetapi berpengaruh pada penggeseran penekanan bobot berita dan pilihan subjek dalam sebuah berita. Sudut pandang, penekanan bobot, dan pilihan subjek utama berita dalam sebuah media, sering kali dapat menjadi ciri khas penulisan media tersebut. Ciri khas penulisan sebuah media, seringkali menjadi alasan bagi khalayak untuk lebih memilih media mana yang dipercaya [17]–[19].
304 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Gambar 2: Top users paling berpengaruh membahas isu COVID-19 di
Jawa Timur [16] Sehingga sering dijumpai beberapa portal berita daring mem-
berikan informasi yang berbeda satu dengan lainnya. Portal berita A dengan portal berita B meliput peristiwa yang sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan judul berita atau perbedaan penulisan headline. Bahkan dapat juga mengutip narasumber yang berbeda, sehingga memiliki perspektif isi yang berbeda. Belum lagi apabila melibatkan gaya penulisan jurnalis yang tentu saja tidak akan sama satu dengan lainnya [20]. Hal ini dapat mempengaruhi penonjolan pemberitaan sebuah fakta. Ada bagian yang ingin ditonjolkan, ada bagian yang perlu dihilangkan, ada beberapa bagian yang patut ditekankan. Pilihan-pilihan semacam itu mengarah pada sebuah konsep yang disebut framing. Analisis framing berguna untuk membedah cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta [21]–[24].
Untuk dapat mengetahui bagaimana ketiga media daring diatas (detik.com, kompas.com dan e100ss) membingkai pemberitaan tentang PSBB Surabaya Raya dihentikan, salah satu analisis framing yang dapat digunakan adalah model analisis dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini membagi sebuah berita menjadi 4 struktur, struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik atau kohesi dan koherensi, struktur retoris atau penggunaan kata, idiom, gambar dan grafik. Apabila menggunakan model analisis framing ini, sebuah berita dapat bedah prosesnya sehingga memahami pesan apa yang lebih menonjol, dan informasi apa yang ditempatkan lebih penting dari yang lain. Tujuannya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 305
agar khalayak lebih memiliki perhatian pada pesan yang ditonjolkan [22]. Berikut ini adalah operasionalisasi empat dimensi struktural teks berita:
Tabel 1: Kerangka Framing Pan dan Kosicki
Struktur Perangkat Framing Unit yang diamati
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta
1. Skema berita
Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta
2. Kelengkapan berita
5W+1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta
3. Detail 4. Maksud
kalimat, hubungan
5. Nominalisasi antara kalinat
6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti
Paragraf, proposisi
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta
9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian
Kata, idiom, gambar/foto, grafik
Sumber: [25] Asumsi analisis framing Zhongdang Pan dan Gerarld M. Kosicki
adalah bahwa pada setiap berita mempunyai bingkai yang berfungsi dari organisasi ide. Framing berhubungan dengan makna, seperti memaknai suatu pertistiwa dilihat dari sebuah tanda yang dimunculkan dalam teks. Framing dalam berita dapat membangun wacana dalam masyarakat, memperkuat preferensi persetujuan atau penolakan terhadap isu tertentu [24]. Data penelitian diperoleh dengan menelusuri dan mengunduh berita yang relevan dengan PSBB Surabaya Raya sejak awal pemberla-kuan hingga penghentian pemberlakuan PSBB Surabaya Raya. Pilihan berita-berita dari detik.com, kompas.com, dan e100ss yang dianalisis adalah pada rentang waktu kegiatan rapat evalusi PSBB, press conference, dan wawancara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang persetujuan keputusan tiga pemimpin daerah di Surabaya yang menolak perpanjangan PSBB Surabaya Raya [26], yaitu pada tanggal 8 dan 9 Juni 2020. Pasca konferensi pers tersebut, ketiga media secara berimbang
306 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menuliskan berita lanjutan yang memiliki keterkaitan dengan penghen-tian PSBB Surabaya Raya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan constructionist yang menempatkan peneliti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek [23]. Relevansi utama dari teori constructionist di dalam penelitian adalah tentang penjelasan bahwa bahasa (language) yang terdapat didalam berita berupa kumpulan dari signs (artikel, foto, video, kalimat) memiliki arti (meaning) dan dapat merepresentasikan budaya (culture) yang ada di masyarakat kita, termasuk media. Dasar pendekatan constructionist berasal dari Teori Representasi Stuart Hall tentang penggunaan bahasa (language) untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (meaningful) kepada orang lain. Ini mengartikan bahwa representasi adalah mengartikan konsep yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Teori representasi memiliki tiga pendekatan, yaitu reflective approach, intentional approach, dan constructionist approach [27]. Framing Berita dan Rekonstruksi Realitas
Tiap portal berita atau tiap penerbitan pers mempunyai gayanya sendiri dalam pemuatan berita. Faktor yang paling berpengaruh adalah perbedaan kebijakan redaksional, karena menentukan cara penulisan berita, cara memaparkan hasil wawancara, pilihan kata yang digunakan, hingga penentuan narasumber berita [28]. Karena sifat dan fakta dari pekerjaan media penyampai berita adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media sesuungguhnya adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality) [29]. Rekonstruksi realitas ke dalam berita, secara teori merupakan bagian dari pendekatan konstruksionis. Pendekatan ini secara spesifik memiliki dua ciri, (1) pertama adalah penekanan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang menggambarkan realitas tersebut. (2) kedua memandang pembentukan pesan sebagai proses dinamis, tentang makna individu sebagai penyampai dan sebagai penerima pesan atau berita. Berita bukanlah mirror of reality yang menampilkan fakta apa adanya [30], [31].
Karena penelitian ini memiliki asumsi bahwa berita merupakan hasil sebuah konstruksi maka peneliti menampilkan data hasil ekspos Gubernur-Gubernur di pulau Jawa dan Walikota/Bupati di Jawa Timur yang diperoleh dari Indonesia Indicator periode 19 Juni 2020, untuk mengetahui apakah benar dari konstruksi yang di buat oleh berita tersebut juga masuk kedalam salah satu data. Sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Indonesia Indicator, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
New Normal, Kajian Multidisiplin | 307
Parawansa tercatat mendominasi figur yang paling banyak terekspos (terpegah) di media daring. Karena setiap hari Khofifah memiliki rutinitas untuk menginformasikan perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur kepada wartawan melalui daring. Sosok Khofifah telah tampil dalam 5.536 berita terkait isu COVID-19. Bahkan tercatat ada 14.554 pernyataan terkait virus corona dari Khofifah Indar Parawansa yang dikutip oleh media daring [32].
Gambar 3: Ekspos berita COVID-19 oleh pimpinan daerah di Jawa
Timur [32]
Framing Berita di Detik.com
Berita di detik.com lebih menyoroti tentang belum layaknya tiga daerah di Surabaya Raya menghentikan pemberlakuan PSBB. Cara yang ditempuh detik.com adalah menampilkan pernyataan dari narasumber Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi FKM Unair Windhu Purnomo. Sikap dan kepuusan tiga kepala daerah, lebih didasari kepentingan politis dan tidak semata-mata kesehatan, sehingga tidak memperpanjang PSBB. Terlebih menurut analisisnya, masyarakat kota di Surabaya teruatam sudah alergi dengan istilah PSBB, bahkan sudah tidak peduli lagi. PSBB diberlakukan atau tidak, masyarakat tidak merasakan bedanya.
Berdasarkan kajian dan analisis epidemiologi, PSBB Surabaya Raya belum selayaknya dilonggarkan karena angka penularannya masih tinggi meskipun jumlahnya sudah turun. Turun bukan berarti sudah
308 | New Normal, Kajian Multidisiplin
aman. Surabaya Raya seharusnya belum boleh longgar. Sebaiknya tetap ada pengawasan ketat seperti PSBB tetapi dengan nama lain, yang lebih diterima oleh masyarakat seperti istilah transisi di Jakarta atau dengan nama apapun, asalkan tidak langsung diberikan kelonggaran. Dikhawa-tirkan berkembangnya penularan baru. Ketiga kepala daerah sebaiknya membuat strategi baru, dengan pemberdayaan masyarakat.
Selain ahli epidemiologi, narasumber lain yang muncul sebagai aktor dalam berita-berita di detik.com adalah Heru Tjahjono dalam kapa-sitasnya sebagai komandan satgas penanggulangan COVID-19 Pem-prov Jatim. Pernyataan Heru mendominasi keseluruhan isi berita. Detik.com menunjukkan ketegasannya bahwa untuk urusan PSBB Surabaya Raya, pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan pernyataan adalah komandan Satgas COVID-19 Pemprov Jatim.
Pada bagian judul cukup tegas dan mengundang pembaca untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal pada bagian judul tersebut. Leadnya menjelaskan dengan baik ,yaitu Kajian Heru tentang tempat yang ramai dikunjungi dann tidak mematuhi aturan/ protokol saat PSBB. Detik.com melalui pernyataan Heru Tjahjono menyoroti mash banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di kota Surabaya, terutama pada beberapa tempat keramaian. Publik harusnya patuh dan menujukkan perubahan kebiasaan. Nada kekhawatiran dan keraguan detik.com terwakili oleh pernyataan-pernyataan Heru Tjahjono, bagai-mana akan menerapkan new normal jika public masih melanggar, tidak patuh protocol kesehatan, di tempat ramai masih tidak bersedia bermasker. Banyak lokasi-lokasi keramaian yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Beberapa tempat kursus, kampus, dan sekolah masih ada 16,9 persen yang aktif. Sekitar 75 persen aktivitas di lembaga pendidikan tersebut tidak memakai masker dan 80 persen tidak menerapkan physical distancing. Sedangkan berbagai tempat ibadah malah sudah bergerak menuju pembenahan diri dengan terus berubah menuju penerapan protokol kesehatan.
Proses penghentian PSBB Surabaya, akan diawali oleh Kabupaten Gresik, kemudian Kabupaten Sidoarjo, terakhir adalah Kota Surabaya. Pada masa persiapan menuju new normal, nantinya harus ada pakta integritas bagi ketiga daerah di Surabaya Raya untuk menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Masyarakat harus dididik, dan dilindungi dengan cara diajak bekerjasama untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Apabila masyarakat patuh dan disiplin menjaga kesehatan, memakai masker,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 309
dan physical distancing, tindakan-tindakan tersebut merupakan vaksin untuk perlindungan tubuh.
Framing Berita di kompas.com
Berita di kompas.com, memiliki ketidaksesuain antara judul dan foto, dengan isi berita. Pada judul berita menyebutkan nama Khofifah, demikian juga dengan pemasangan foto Khofifah sedang berbicara di depan microphone, namun pada isinya sama sekali tidak menyebutkan kutipan pernyataan Khofifah Indar Parawansa. Kompas.com justru menggunakan narasumber lain yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono yang menjelaskan hasil press conference Gubernur Jawa Timur tersebut kepada media. Sebagai Komandan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Pemprov Jatim, Heru Tjahjono menyampai-kan bahwa tiga kepala daerah Surabaya Raya (Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, dan Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin) bersepakat mengakhiri PSBB Surabaya Raya, pada hari Senin, 8 Juni 2020 bertempat di Gedung Negara Grahadi. Ketiga kepala daerah Surabaya Daerah melakukan rapat evaluasi bersama Gubernur Jawa Timur yang berperan sebagai fasilitator. Alasan utama ketiga kepala derah tersebut adalah permasalahan ekonomi. Ketiganya berpendapat bahwa roda ekonomi harus tetap bergerak agar masyarakat dapat bertahan di tengah kondisi pandemi.
Sorotan khusus kompas.com adalah pernyataan walikota Surabaya yang menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sudah menyiapkan protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan masyarakat jika PSBB Surabaya tak diperpanjang. Kompas.com tidak menampilkan pernyataan bupati Gresik dan plt. bupati Sidoarjo. Pernyataan-pernyataan Tri Rismaharini menjadi fokus berita, mengesankan bahwa walikota Surabaya ini menjadi inisiator atas dihentikannya pemberlakuan PSBB Surabaya Raya. Sebagaimana pernyataannya sehari sebelumnya (7 Juni 2020) di Gelora Bung Tomo bahwa Risma bersama kedua temannya (bupati Gresik dan Plt. Bupati Sidoarjo) sudah membahas usulan tidak diperpanjangnya PSBB Surabaya Raya dan tinggal menyodorkan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur pada rapat evaluasi pada tanggal 8 Juni 2020.
Pada berita lain Tri Rismaharini tetap menjadi tokoh utama. Sudut pandang kompas.com menilai bahwa penghentian PSBB Surabaya merupakan persetujuan Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa. Sedangkan ketiga kepala daerah Surabaya Raya hanya sebatas mengusulkan. Keputusan penghentian PSBB Surabaya Raya oleh
310 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Risma digeser maknanya sebagai pemberian amanah dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Berbeda dengan detik.com dan e100ss yang menegaskan posisi Gubernur Jawa Timur adalah menjadi fasilitator dan mediator atas keinginan ketiga kepala daerah Surabaya Raya untuk tidak melanjutkan perpanjangan PSBB Surabaya Raya. Waalikota harus menjalani keputusan yang disetujui Gubernur Jawa Timur. Penghentian PSBB Surabaya dinilai Risma lebih berat, sehingga seluruh warga kota tidak boleh lengah dan sembrono. Warga kota dihimbau untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan setelah PSBB berakhir.
Pada bagian lain berita di Kompas.com, memunculkan alasan utama mengapa Risma mengusulkan penghentian PSBB Surabaya Raya. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi agar warga kota Surabaya lebih mudah mencari mata pencaharian di tengah pandemik. Alih-alih menya-takan secara verbal agar masyarakat miskin Surabaya dapat bekerja kembali, justru ada maksud tersirat dengan keberpihakannya kepada kelompok pengusaha. Pernyataan Risma yang secara langsung menye-butkan lebih dulu agar hotel, restoran, mall, dan pertokoan segera menerapkan disiplin protokol kesehatan. Sedangkan “pasar” disebutkan paling akhir. Hal ini menunjukkan prioritas Risma yang sebenarnya dengan pengehentian PSBB Surabaya Raya adalah pengusaha dan lokasi-lokasi bisnis besar semata dan bukan warga miskin dan pasar. Terlebih dengan kalimat bahwa sebelumnya sudah banyak pihak yang mengeluh ke Risma ingin kembali menjalani kehidupan normal.
Framing Berita di e100ss
Berita di e100ss dan suarasurabaya.net memberikan penekanan bahwa keputusan penghentian PSBB Surabaya bukan keputusan Pemerintah Provinsi. Langkah itu ditempuh murni oleh inisiatif dan kehendak tiga kepala daerah di Surabaya Raya dan sudah dituangkan dalam draft peraturan kepala daerah masing-masing. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai mediator dalam rapat evaluasi PSBB Surabaya yang berlangsung selama dua jam.
Satu hal yang tidak muncul dari dua berita lain dari detik.com dan kompas.com adalah penekanan pada pentingnya masa setelah penghentian PSBB Surabaya Raya. Bahwa penghentian pemberlakuan PSBB tidak serta merta ketiga daerah tersebut memberikan pelonggaran. Tetapi ada suatu masa yang harus dilakukan sebelum penerapan pelong-garan new normal yaitu disebut masa transisi. Masa transisi ini harus dimuat di dalam Peraturan Bupati dan Wali Kota yang menghentikan PSBB. Untuk itulah, ketiga kepala daerah masih akan mendiskusikan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 311
dengan tim masing-masing untuk merumuskan pemuatan masa transisi itu di dalam peraturan kepala daerah yang memuat tentang masa transisi itu akan didiskusikan oleh perwakilan masing-masing kepala daerah. Bahkan pemprov Jatim telah melakukan pembahasan bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim, terkait penerapan masa transisi yang akan berlangsung di Surabaya Raya selama 14 hari. Sebelum penerapan new normal.
Senada dengan detik.com, berita di e100ss lebih menyoroti apa yang sebaiknya dilakukan setelah PSBB Surabaya Raya dihentikan. Narasumber yang dikutip oleh e100ss adalah Tri Rismaharini yang menyatakan bahwa warga Kota Surabaya harus bersiap menghadapi kebiasaan baru dan mencegah bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Jika warga kota Surabaya menginginkan new normal, harus konsekuen untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan. Tri Rismaharini berjanji akan mengatur mengatur protokol ketat dan detail bagi berbagai lini usaha dan aktivitas warga di tengah transisi new normal ini. Pernyataan ini menunjukkan inkonsistensi Tri Rismaharini pasca penghentian PSBB Surabaya, pada satu kesempatan disebut sebagai new normal, sedangkan pada pernyataan berikutnya menyebutnya sebagai masa transisi new normal.
Pernyataan-pernyataan Tri Rismaharini yang dikutip dalam berita lain di e100ss, menunjukkan keberpihakan sebenarnya walikota Surabaya. Seperti berita di kompas.com, lokasi keramaian yang menjadi sorotan Walikota Surabaya adalah Mall dan bukan pasar. Sebagaiamana himbauannya agar para pengunjung mall, sebelum masuk wajib mengenakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak saat berada di dalam mall, dan dilarang masuk dulu apabila pengunjung mall penuh. Termasuk permintaannya agar semua hotel, restoran, mall, pertokoan, pusat perdagangan, pasar, perbengkelan, dan pekerjaan konstruksi di kota Surabaya harus menghormati dan mentaati protokoal yang telah dibuat oleh pemerintah. Tri Rismaharini juga mengajak warga Surabaya untuk saling menjaga dan membuktikan bahwa kota Surabaya siap menghadapi new normal.
Berita di e100ss juga menampilkan apa adanya tentang pernya-taan walikota Surabaya yang menggeser makna penghentian PSBB Surabaya sebagai amanah dari Gubernur Jawa Timur. Seakan-akan Tri Rismaharini dan warga kota Surabaya mendapat kepercayaan dari Gubernur dan Forpimda Jatim untuk tidak memperpanjang PSBB Surabaya sehingga dapat menjalani kehidupan normal. Padahal warga
312 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Surabaya bahkan Jawa Timur mengetahui bahwa senyatanya penghen-tian PSBB Surabaya adalah keputusan dari tiga kepala daerah di Surabaya Raya (Walikota Surabaya, Bupati Gresik, dan Plt, Gubernur Sidoarjo) dan bukan keputusan Gubernur Jawa Timur. Sehingga dengan kepercayaan tersebut, seluruh warga kota Surabaya tidak boleh ceroboh dan dihimbau untuk bisa menjalani kehidupan dan bekerja dengan penuh kehati-hatian, tidak bebas sepenuhnya, dan tidak bisa rea-reo (bahasa Surabaya yang artinya berkumpul) seenaknya sendiri. Penutup
Hasil keseluruhan analisis framing menunjukkan perbedaan konstruksi fakta yang dilakukan oleh detik.com, kompa.com, dan e100ss melalui suarasurabaya.net. detik.com mengungkap kekecewaan tersem-bunyi Gubernur Jawa Timur atas selesainya PSBB di Surabaya Raya yang diputuskan oleh tiga pimpinan daerah. Serta mengungkap bahwa penghentian PSBB Surabaya Raya semata-mata alasan politik yaitu penolakan terhadap desakan Gubernur Jatim yang bermaksud menekan angka penularan COVID-19 di Jawa Timur secara umum, karena kota Surabaya telah berubah menjadi epicentre baru setelah Jakarta berhasil dikendalikan. Detik.com juga menunjukkan bahwa secara hitungan statistik, kota Surabaya belum selayaknya menghentikan pemberlakukan PSBB. Kompas.com lebih menyoroti waikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai figur sentral dalam penghentian PSBB Surabaya Raya. Sedangkan e100ss mengungkap faktor ekonomi sebagai alasan sebenarnya dibalik penghentian PSBB oleh tiga pimpinan daerah. Serta keberpihakan Tri Rismaharini lebih kepada kepentingan para pengusaha yang meng-inginkan ekonomi Surabaya kembali normal.
Struktur sintaksis dan struktur skrip dalam teks berita dari detik.com dan e100ss telah menunjukkan konsistensi antara judul berita dengan isi beritanya. Semua teks beritanya mengandung kelengkapan latar penyampaian berita dan ketersediaan sumber berita. Seluruh struktur headline-nya telah mencamtumkan nama media, tempat, tanggal peristiwa, dan unsur 5W dan 1 H (What, Who, When, Where, Why, and How). Sedangkan struktur sintaksis dan skrip pada subjek berita di kompas.com, meninggalkan sebagian dari unsur 5W dan 1H. Serta ada ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita.
Struktur tematik pada teks berita detik.com dan e100ss memberikan penekanan pada kekhawatiran pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila PSBB di Surabaya Raya tidak diperpanjang masa pemberlakuannya. Kekhawatiran tersebut diwujudkan dengan menyajikan berita yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 313
berisi ulasan ahli epidemiologi mengenai layak tidaknya PSBB Surabaya Raya dihentikan, serta pemaparan komandan Satgas COVID-19 Pemprov Jatim tentang berbagai fakta tentang banyaknya warga Surabaya dan sekitarnya yang melanggar protokol kesehatan. Sedangkan kompas.com lebih menekankan pada kesiapan warga Kota Surabaya untuk menghadapi kehidupan normal di tengah pandemi.
Rujukan
[1] Kemlu RI, ‘Pernyataan Pers Kemlu tentang Update Pemulangan WNI dari Wuhan serta Kebijakan Pemri mengenai Pendatang/Traveler dari RRT’, Negara Melindungi, 2020. [Online]. Available: https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt. [Accessed: 25-Jun-2020].
[2] Kemenkes RI, ‘Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)’, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Jakarta, p. 135, 2020.
[3] Media Center COVID-19, ‘Live: Keterangan Pers Juru Bicara Covid-19’, Sekretariat Presiden, Jakarta, 2020.
[4] C. Lova, ‘PSBB Jakarta Mulai 10 April: Belajar Tetap di Rumah, Fasilitas Umum Ditutup’, kompas.com, 2020. [Online]. Available: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/07/21552791/psbb-jakarta-mulai-10-april-belajar-tetap-di-rumah-fasilitas-umum-ditutup. [Accessed: 01-Jul-2020].
[5] P. Ariefana, ‘Data 65 Warga Jawa Timur Suspect Virus Corona, Ini Penjelasan Dinkes’, jatim.suara.com, 2020. [Online]. Available: https://jatim.suara.com/read/2020/03/05/140546/data-65-warga-jawa-timur-suspect-virus-corona-ini-penjelasan-dinkes. [Accessed: 15-Jun-2020].
[6] A. Faizal, ‘Risma dan 2 Kepala Daetah Lainnya Sepakat Akhiri PSBB Surabaya Raya, Khofifah Fasilitator’, kompas.com, 2020. [Online]. Available: https://regional.kompas.com/read/2020/06/08/21172681/risma-dan-2-kepala-daerah-lainnya-sepakat-akhiri-psbb-surabaya-raya-khofifah?page=all#page2. [Accessed: 22-Jun-2020].
[7] Jatimprov.go.id, ‘Data Pemantauan COVID-19 Kota Surabaya’,
314 | New Normal, Kajian Multidisiplin
infocovid19.jatimprov.go.id, 2020. [Online]. Available: http://infocovid19.jatimprov.go.id/index.php/data. [Accessed: 07-Jun-2020].
[8] Z. A. Achmad and R. Ida, ‘The shifting role of the listeners in the mediamorphosis process of culture radio: A case study of Jodhipati 106.1 FM’, Masyarakat, Kebud. dan Polit., vol. 32, no. 3, p. 240, 2019.
[9] Z. A. Achmad, ‘Integrasi Program Dakwah dan Budaya: Studi Etnografi Virtual Mediamorfosis Radio Nada FM Sumenep Madura’, J. Komun. Islam, vol. 09, no. 2, pp. 238–263, 2019.
[10] R. Fidler, Mediamorphosis: Understanding New Media. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1997.
[11] Z. A. Achmad, ‘Mediamorphosis: Understanding New Media (review)’, in Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19, E. R. Nawangsari and A. Kriswibowo, Eds. Surabaya: Penerbit Administrasi Negara, 2020.
[12] K. C. S. Sinaga, ‘Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah Di Kompas.Com Dan Merdeka.Com’, Jom FISIP, vol. 5, 2016.
[13] S. S. Alamiyah and Z. A. Achmad, ‘The Role of Citizen Journalism in Creating Public Sphere in Indonesia’, in Strengthening Democratic Accountability for Creating Good Governance, 2015, pp. 162–167.
[14] A. Sehl, A. Cornia, and R. K. Nielsen, ‘Public Service News and Digital Media’, SSRN Electron. J., 2016.
[15] T. Flew, New Media: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005.
[16] academic.droneemprit.id, ‘Twitter Top Users by Impact, Isu COVID-19 Di Jawa Timur’, Drone Emprit Academic, 2020. [Online]. Available:https://academic.droneemprit.id/-/search/view/ analysis/twitter/sub/user_by_impact/id/838. [Accessed: 07-Jun-2020].
[17] F. Fensi, ‘Paradoxic Language “Cebong-Kampret” in Facebook As a Mirror of the Political Language of Indonesia’, Bricol. J. Magister Ilmu Komun., vol. 5, no. 02, p. 103, 2019.
[18] S. Livingstone, ‘Relationships between media and audiences: prospects for audience reception studies’, Media, Ritual Identity Essays Honor Elihu Katz, pp. 1–12, 1998.
[19] Z. Pan and G. M. Kosicki, ‘Assessing News Media Influences on the Formation of Whites’ Racial Policy Preferences’, Communic. Res., vol. 23, no. 2, pp. 147–178, Apr. 1996.
[20] Z. A. Achmad, ‘Sikap Masyarakat Muslim Pelaku Yoga di Surabaya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 315
tentang Berita Fatwa MUI Haramkan Yoga’, J. Ilmu Komun., vol. 1, no. 2, pp. 111–120, 2009.
[21] W. Gamson, D. Croteau, W. Hoynes, and T. Sasson, ‘Media Images and the Social Construction of Reality’, Annu. Rev. Sociol., vol. 18, no. 1992, pp. 373–393, 2016.
[22] Z. Pan and G. M. Kosicki, ‘Framing analysis: An approach to news discourse’, Polit. Commun., vol. 10, no. 1, pp. 55–75, 1993.
[23] S. Setiawan, A. M. Huda, and G. Mardana, ‘POLITICAL COMMUNICATION IN THE MASS MEDIA (Framing Analysis News of East Java Governor Election 2013 on Malang Daily Morning Post and Memo Arema at 12th up to 26th August 2013 Period)’, JARES (Journal Acad. Res. Sci., vol. 1, no. 2, p. 1, Mar. 2016.
[24] I. M. A. Wiranata, S. Mardliyah, and Z. A. Achmad, ‘The Contestation of Discourses on Sustainable Development in the Controversy of Benoa Bay Reclamation’, in International Conference on Contemporary Social and Political Affair 2016. RE-EXAMINING GOVERNANCE: STRENGTHENING CITIZENSHIP IN THE CHANGING WORLD, 2016, no. November.
[25] Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
[26] Kompas TV, ‘Breaking News, PSBB Surabaya Raya Berakhir’, Kompas TV, Indonesia, 2020.
[27] S. Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications and The Open University, 1997.
[28] Z. A. Achmad, Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia, 2nd ed. Surabaya: Lutfansah, 2014.
[29] A. Subur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
[30] T. Bennett, ‘Media, “reality”, signification’, in Culture, society and the media, M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, and J. Woollacott, Eds. London and New York: Routledge, 1982, pp. 285–306.
[31] M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, and J. Woollacott, Eds., Culture, society and the media. London and New York: Routledge, 1982.
[32] I. Indicator, ‘Perempuan-Perempuan Terpegah dan Tervokal selama pandemi COVID-19’, Release, 2020. [Online]. Available: http://www.indonesiaindicator.com/99-publication/release.html. [Accessed: 23-Jun-2020].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 319
Bab 20
Kelor (Moringa Oleifera), Penguat Imun Tubuh di Masa Pandemi Covid-19 Eny Dyah Yuniwati24
Pengantar
Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang sudah tumbuh dan berkembang di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini juga mudah tumbuh pada semua jenis tanah dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan [1]. Kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis pada semua jenis tanah, tahan terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan serta mudah dibiakkan dan tidak memerlukan perawatan yang intensif [2].
Pemanfaatan tanaman kelor di Indonesia saat ini masih terbatas. Masyarakat biasa menggunakan daun kelor sebagai pelengkap dalam masakan sehari-hari, bahkan tidak sedikit yang menjadikan tanaman kelor hanya sebagai tanaman hias yang tumbuh pada teras-teras rumah, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia pemanfaatan daun kelor lebih banyak untuk memandikan jenazah, meluruhkan jimat, dan sebagai pakan ternak [3]. Padahal menurut [4] tanaman kelor memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat, sehingga sangat berpotensi digunakan dalam pangan, kosmetik dan industri.
Terdapat beberapa julukan untuk pohon kelor, antara lain; The Miracle Tree, Tree For Life dan Amazing Tree. Julukan tersebut muncul karena bagian pohon kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit, batang, hingga akar memiliki manfaat yang luar biasa. Dimana tanaman Kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, asam amino, antipenuaan, dan antiinflamasi. Kelor mangandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional afrika dan india serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencagah lebih dari 300 penyakit, berbagai bagian dari tanaman kelor bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, memiliki antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiinflamasi, antiulcer, diuretik,
24 Dr. Eny Dyah Yuniwati, SP. MP. , Dosen Program Studi Agroteknologi, Universitas
Wisnuwardhana , Malang
320 | New Normal, Kajian Multidisiplin
antihipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, antidiabetik, anti-bakteri dan antijamur [5]. aktivitas antioksidan dan kandungan total fenolik ekstrak daun kelor (Moringa oleifera Lam) [6].
Manfaat dan khasiat tanaman kelor (Moringa oleifera) terdapat pada semua bangian tanaman baik daun, batang, akar maupun biji. Kandungan nutrisi yang cukup tinggi menjadikan kelor memiliki sifat fungsional bagi kesehatan serta mengatasi kekurangan nutrisi. Oleh karena kelor disebut Miracle Tree dan Mother’s Best Friend. Selain itu kelor berpotensi sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, obat-obatan dan perbaikan lingkungan yang terkait dengan cemaran dan kualitas air bersih [7].
Kelor dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman bergizi dan WHO telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengatasi masalah gizi (malnutrisi) [8]. Di Afrika dan Asia daun kelor direkomendasikan sebagai suplemen yang kaya zat gizi untuk ibu menyusui dan anak pada masa pertumbuhan. Semua bagian dari tanaman kelor memiliki nilai gizi, berkhasiat untuk kesehatan dan manfaat dibidang industri. Melalui fungsi dan manfaat kelor yang sangat banyak dan sangat baik untuk pangan, obat-obatan, maupun lingkungan maka sangat perlu pengembangan dan pengolahan yang kimia sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan bernilai jual tinggi [9].
Pembahasan
Pembuatan Ekstrak daun kelor
Daun kelor mengandung unsur multi zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Enam sendok makan penuh dapat memenuhi kebutuhan zat besi dan kalsium wanita hamil dan menyusui. Kandungan nilai gizi yang tinggi dalam daun kelor juga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui dan balita dalam masa pertumbuhan [9]. Β-caroten yang ditemukan dalam kelor merupakan prekusor retinol (vitamin A). Terdapat 25 jenis Β-caroten pada daun kelor, tergantung dari varitas. Selain vitamin dan mineral daun kelor juga mengandung semua asam amino yang essensial (asam amino yang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus disuplai dari luar tubuh dalam bentuk jadi) [10].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 321
Gambar 1: Tanaman Kelor banyak terdapat di lingkungan Desa
Daun kelor memiliki kandungan karbohidrat, protein, zat besi,
kalsium, Vitamin C, Vitamin A dan kalium yang tinggi (Krisnadi, 2015). Daun kelor dapat dikonsumsi secara langsung sebagai sayuran maupun sebagai fortifikasi bahan pangan [9]. Konsumsi daun kelor merupakan salah satu alternatif untuk menanggurangi kasus kekurangan gizi di Indonesia [11].
Ekstrak daun kelor dapat di buat dengan menimbang sebanyak 50 gram daun kelor segar dihancurkan menggunakan blender, ditambahkan pelarut etanol 96%, dimasukkan ke dalam wadah, ditutup dan dibiarkan selama dua hari terlindung dari sinar matahari. Campuran itu disaring sehingga didapat serbuk. Serbuk di campur dengan etanol 96% menggunakan prosedur yang sama. Serbuk diuapkan dengan menggunakan alat penguap vakum putar pada suhu 40o C. Ekstrak daun kelor selanjutnya dilakukan skrining fitokimia untuk mendeteksi senyawa tumbuhan berdasarkan golongannya. Metode yang telah dikembangkan dapat mendeteksi adanya golongan
322 | New Normal, Kajian Multidisiplin
senyawa alkaloid, fenolat, flavonoid, tanin, saponin dan steroid/triterpenoid.
Gambar 2: serbuk daun kelor
Senyawa bioaktif dalam kelor memyebaban kelor memiliki sifat bahwa daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikrobia. Hal ini menyebabkan kelor dapat berfungsi sebagai pengawet alami dan memperpanjang masa simpan olahan berbahan baku daging yang disimpan pada suhu 40C tanpa terjadi perubahan warna selama penyimpanan. Kandungan nutrisi mikro sebanyak 7 kali vitamin C jeruk, 4 kali vitamin A wortel, 4 gelas kalsium susu, 3 kali potassium pisang, dan protein dalam 2 yoghurt. Oleh karena itu kelor berpotensi sebagai minuman probiotik untuk minuman kesehatan, atau ditambahkan dalam pangan gizinya. Selain daun dan buah, biji kelor juga dapat diolah menjadi tepung atau minyak sebagai bahan baku pembuatan obat dan kosmetik yang bernilai bernilai tinggi [9].
Kandungan nilai gizi yang tinggi, khasiat dan manfaatnya menyebabkan kelor mendapat julukan sebagai Mother’s Best sendiri pemanfaatan kelor masih belum banyak diketahui, umumnya hanya dikenal sebagai salah satu menu sayuran. Selain dikonsumsi langsung dalam bentuk segar, kelor juga dapat diolah menjadi bentuk tepung atau powder yang dapat digunakan sebgai pada berbagai produk pangan, seperti pada olahan pudding, cake, nugget, biscuit, cracker serta olahan lainnya. Menurut [8] tepung daun kelor dapat ditambahkan untuk setiap jenis makanan sebagai suplemen gizi. Berikut ini adalah tabel nilai kadungan gizi daun kelor segar dan kering:
New Normal, Kajian Multidisiplin | 323
Tabel 1: Nilai kadungan gizi daun kelor segar dan kering
Komposisi gizi Daun Segar Daun Kering
Kadar air (%) 94,01 4,09 Protein (%) 22,7 28,44 Lemak (%) 4,65 2,74 Kadar abu - 7,95 Karbohidrat (%) 51,66 57,01 Serat (%) 7,92 12,63 Kalsium (%) 350,550 1600,2200 Energi (Kcal/100g) - 307,30
Sumber: [9] Tabel 2: Kandungan Asam Amino per 100g daun kelor
Komposisi asam amino Daun segar Daun kering
Argine 406,6 mg 1.325 mg Histidine 149,8 mg 613 mg Isoleusine 299,6 mg 825 mg Leusine 492,2 mg 1.950 mg Lysine 342,4 mg l.325 mg Methionine 117,7 mg 350 mg Phenylalanine 310,3 mg 1.388 mg Threonine 117,7 mg 1.188 mg Tryptophan 107 mg 425 mg Valine 374,5 mg 1.063 mg
Sumber: [9] Manfaat tanaman kelor yang luasa biasa ini, dari berbagai
penelitian telah dikelompokkan sebagai berikut:
Sebagai Bahan Pangan
Pada bidang pangan, tanaman kelor telah digunakan untuk mengatasi malnutrisi terutama untuk balita dan ibu menyusui. Daun tanaman kelor dapat dikonsumsi dalam kondisi segar, dimasak, atau disimpan dalam bentuk tepung selama beberapa bulan tanpa pen-dinginan dan tanpa terjadi kehilangan nilai gizi. Proses pengolahan daun kelor menjadi tepung akan dapat meningkatkan nilai kalori, kandungan protein, kalsium, zat besi dan vitamin A. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengolahan daun kelor menjadi tepung akan terjadi pengurangan kadar air yang terdapat dalam daun kelor [12].
Selain pemanfaatan secara tradisional, daun tanaman kelor hingga saat ini dikembangkan menjadi produk pangan modern seperti
324 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tepung kelor, kerupuk kelor, kue kelor, permen kelor dan teh daun kelor. Hal ini didukung oleh hasil penelitian [13] bahwa produk biskuit Moringa Oleifera memenuhi standar SNI pembuatan biskuit dan dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi serta dapat dipertimbangkan sebagai suplemen nutrisi untuk kasus malnutrisi [11]. Bahan dari tanaman kelor juga dapat dicampur dengan bahan lain menjadi tepung komposit yang terbuat dari kedelai, kacang hijau, bayam merah, dan daun kelor yang memiliki kandungan protein dan energi yang memadai untuk dijadikan bahan dasar produk diet tinggi kalori tinggi protein tinggi energi.
Sebagai salah satu bahan pangan, bahan dari tanaman kelor juga dapat dicampur dengan bahan lain menjadi tepung komposit yang terbuat dari kedelai, kacang hijau, bayam merah, dan daun kelor yang memiliki kandungan protein dan energi yang memadai untuk dijadikan bahan dasar produk diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP) yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal [14].
Hampir semua bagian tanaman kelor dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan. Menurut bagian-bagian tanaman kelor yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan antara lain:
a. Batang
Batang tanaman kelor oleh masyarakat dijadikan sebagai pagar hidup yang ditanam di belakang atau di samping rumah. Adapula yang memanfaatkan sebagai tanaman pembatas lahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbatu atau lahan marginal. Bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah kulit batang. Kulit batang dikerik hingga bagian kayu kemudian ditabur di atas daging atau ikan yang sedang direbus.
b. Daun
Daun tanaman kelor dimanfaatkan sebagai sayuran untuk menu sehari-hari. Daun yang masih segar biasanya dipetik dan langsung di masak dengan air dicampur terong dan daun kemangi. Namun, adapula yang mencampur santan dengan daun kelor maupun daun kelor dicampur dengan kacang hijau yang sudah dimasak sebelumnya lalu dijadikan sebagai menu sehari-hari yang dihidangkan dengan nasi.
c. Buah
Sebagaimana pemanfaatan daun tanaman kelor, maka buah tanaman kelor juga merupakan menu yang diolah sebagai sayuran sehari-hari dalam bentuk sayur bening ataupun dicampur santan. Buah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 325
tanaman kelor yang berbentuk memanjang (Gambar 2) terlebih dahulu dibersihkan kulitnya lalu dipotong-potong dengan ukuran sekitar 5 cm, selanjutnya potongan buah tanaman kelor diolah bersama bahan lain seperti terong atau kacang panjang tergantung pada selera penikmatnya. Ada juga sebagian masyarakat yang membelah buah tanaman kelor, lalu isinya diserut, selanjutnya diolah bersama bahan lain seperti kacang hijau dan santan menjadi menu sayuran sehari-hari.
Sebagai Fungsi Kesehatan
Beberapa komponen yang terkandung dalam bagian tanaman kelor (Tabel 1) dapat memberikan efek kesehatan berupa: 1) Menurunkan berat badan: memberikan efek kepada tubuh agar
merangsang dan melancarkan metabolisme sehingga dapat membakar kalori lebih cepat.
2) Anti diabetes: daun kelor memiliki sifat anti diabetes yang berasal dari kandungan seng yang tinggi seperti mineral yang sangat di butuhkan untuk memproduksi insulin, sehingga daun kelor dapat bermanfaat sebagai anti diabetes yang signifikan.
3) Mencegah penyakit jantung: dapat menghasilkan lipid terosidari lebih rendah serta memberikan perlindungan pada jaringan jantung dari kerusakan struktural.
4) Menyehatkan rambut: dapat menyehatkan rambut, karena daun kelor dapat membuat pertumbuhan rambut menjadi hidup dan mengkilap yang dikarenakan asupan nutrisi yang lengkap dan tepat.
5) Menyehatkan mata: Daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang tinggi sehingga jika kita mengkonsumsinya secara rutin dapat membuat penglihatan menjadi jernih dan menyehatkan mata. Sedangkan untuk pengobatan luar dapat menggunakan rebusan dari daun kelor untuk membasuh mata yang sedang sakit, atau juga dengan cara lain yaitu siapkan 3 tangkai daun kelor kemudian tumbuklah dan masukan ke dalam segelas air dan aduklah. Lalu diamkan agar mengendap, jika sudah mengendap maka air tersebut dapat dijadikan obat tetes untuk mata.
6) Mengobati rematik: rematik terjadi dikarenakan tulang yang kekurangan nutrisi. Daun kelor memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan kalsium di dalam tulang. Daun kelor juga bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada persendian dikarenakan oleh penumpukan asam urat.
7) Mengobati Herpes/Kurap: Herpes adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh virus golongan famili hepertoviridae, yang
326 | New Normal, Kajian Multidisiplin
akan menimbulkan bintik - bintik merah dengan disertai nanah. Cara untuk mengobatinya adalah dengan menyiapkan 3-7 tangkai daun kelor lalu ditumbuk hingga halus dan tempelkan langsung pada kulit yang terkena.
8) Mengobati penyakit dalam seperti luka lambung, luka usus dan batu ginjal: Batu ginjal merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan pada saluran kemih. Daun kelor dapat memperlancar pencernaan sehingga dengan mengkonsumsi daun kelor yang telah dijadikan masakan secara rutin akan meluruhkan batu ginjal. [15].
Menurut kelor mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan. Selanjutnya beliau menganjurkan agar minum rebusan daun kelor selagi air masih hangat sebab, efek antioksidan masih kuat dalam keadaan hangat. Kelor memiliki energi dingin sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit dengan energi panas atau kelebihan energi seperti radang atau kanker. [16].
Hasil uji fitokimia pada daun kelor (Moringa oleifera L.) menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid. Fungsi senyawa alkaloid bagi tumbuhan adalah sebagai zat racun untuk melawan serangga atau hewan pemakan tanaman dan sebagai faktor pengaruh pertumbuhan. Kegunaan lain dari senyawa ini di bidang farmakologi sebagai stimulan sistem saraf, obat batuk, obat tetes mata, sedative, obat malaria, kanker, dan anti bakteri.
Uji fitokimia flavonoid ekstrak daun kelor menunjukkan hasil positif. Pada tumbuhan, flavonoid berfungsi pada proses fotosintesis, anti mikroba, anti virus. Pada manusia flavonoid berfungsi sebagai antibiotika, misalnya pada penyakit kanker dan gangguan ginjal. Beberapa jenis flavonoid seperti slimirin dan silyburn terbukti mengobati gangguan fungsi hati, menghambat sintesis prostaglandin sehingga bekerja sebagai hepatoprotektor. Flavonoid juga bekerja mengurangi pembekuan darah.
Fenolat sebagian besar adalah antioksidan yang menetralkan reaksi oksidasi dari radikal bebas yang dapat merusak struktur sel dan berkontribusi terhadap penyakit dan penuaan. Peranan beberapa golongan senyawa fenol sudah diketahui, misalkan senyawa fenolik atau polifenolik merupakan senyawa antioksidan alami tumbuhan. Senyawa tersebut bersifat multifungsional dan berperan sebagai antioksidan karena mempunyai kemampuan sebagai pereduksi dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 327
penangkap radikal bebas [17].Berikut disertakan hasil uji Fitokimia pada Daun Kelor
Tabel 3. Hasil Uji Fitokimia pada Daun Kelor (Moringa oleifera L.)
No. Uji Fitokomia Pereaksi Perubahan Warna Keterangan
1 Alkaloid HCl 2N + pereaksi Wagner
Terbentuk endapan coklat
Alkaloid (+)
2. Flavonoid Bate Smith-Metcalfe
Hijau kecoklatan menjadi hijau kekuningan
Flavonoid (+)
NaOH 10% Hijau kecoklatan menjadi hijau kekuningan
3. Saponin Akuades, dipanaskan, kocok + HCl 2N
Tidak terbentuk busa yang stabil
Saponin (-)
4. Fenolat FeCl3 Hijau kecoklatan menjadi biru kehitaman
Fenolat (+)
5. Triterpenoida/ Steroida
Lieberman-Burchard
Hijau kecoklatan menjadi hijau keunguan
Triterpenoid/ steroid (+)
H2SO4 Hijau kecoklatan menjadi hijau keunguan
6. Tannin FeCl3 Hijau kecoklatan menjadi biru kehitaman
Tannin (+)
Gelatin Terbentuk endapan
Ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera L.) mengandung senyawa aktif steroid dan triterpenoid. Senyawa tannin berfungsi sebagai antioksidan dan penghambat pertumbuhan tumor [18]. Saponin merupakan glikosida dari steroid, steroid alkaloid, atau steroid dengan suatu fungsi nitrogen maupun triterpinoid ditemukan pada tanaman. Charantin, suatu saponin steroid diisolasi dari Momordicha charantia dilaporkan menimbulkan suatu aktivitas seperti insulin, dengan me-ningkatkan pelepasan insulin dan memperlambat proses glukogenesis beta sitostero.
Manfaat kelor dapat didapatkan dengan berbagai olahan dalam berbagai bidang baik dari bidang pangan, bidang tanaman, maupun
328 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bidang kesehatan, sehingga memperkuat imun tubuh manusia. Apabila di konsumsi maka akan dapat menguatkan senyawa senyawa dalam tubuh kita. Di sisi lain biji kelor juga mengandung senyawa bioaktif rhamnosyloxy-benzil-isothiocyanate, yang mampu mengadopsi dan mene-tralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang dalam air, sehingga sangat potensial digunakan sebagai koagulan alami untuk membersih-kan air dari ion-ion logam terlarut.
Buah kelor dipetik kemudian dipisahkan dari kulitnya dan dikeringkan, selanjutnya ditumbuk hingga menjadi serbuk dan diayak hingga diperoleh ukuran 180 μm, 250 μm, 355 μm, 420 μm dan 600 μm. Sebanyak 0,5 gram serbuk biji kelor tersebut kemudian dicampur dengan 50 ml air yang mengandung 10 ppm ion besi, diaduk selama 2 menit agar proses sempurna, selanjutnya disaring dan sisa kadar besi yang terdapat dalam filtrat ditentukan dengan metode spektrofotometri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makin kecil ukuran serbuk biji kelor ternyata kemampuannya untuk mengadopsi ion besi dalam air semakin besar, demikian juga usia ternyata ikut menentuakan kemampuan biji kelor untuk mengadopsi ion-ion besi dalam air. Pengurangan kadar ion besi yang paling besar terjadi pada penggunaan ukuran butir 180 μm dari biji kelor yang berusia muda yaitu sebesar 874 μg besi/gram biji kelor [19].
Dari berbagai bahasan di atas terbukti bahwa kelor adalah salah satu tanaman yang mampu menjaga metabolisme tubuh, anti diabetes, mencegah penyakit jantung, menyehatkan rambut, menyehatkan mata karena mempunyai kandungan vitamin A yang tinggi. Selain itu daun kelor juga mengandung kalsium yang tinggi, mengobati berbagai luka dalam, meluruhkan batu ginjal, mengandung anti oksidan tinggi dan mengobati kanker. Dari berbagai uji yang di lakukan terhadap kelor, bahwa senyawa alkaloid, yang berfungsi sebagai stimulan system saraf, obat batuk, obat stress, obat malaria dan anti bakteri. Uji Flavonoid kelor juga terbukti positif mengobati gangguan fungsi hati, dan pembekuan darah. Uji fenolat pada kelor menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung antioksidan yang tinggi sehingga bisa mengoksidasi radikal bebas. Ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera L.) mengan-dung senyawa aktif steroid dan triterpenoid, tannin, saponin steroid yang berfungsi seperti insulin dan menghambat glukogenesis.
Kompleksnya kandungan senyawa di tanaman kelor mempu-nyai pengaruh yang luar biasa terhadap perbaikan imun tubuh di masa
New Normal, Kajian Multidisiplin | 329
pandemic covid ini, sehingga dapat di jadikan alternative obat dan vitamin penguat imun tubuh.
Penutup
Dari berbagai bahasan di atas dapat di simpulkan bahwa tanaman kelor mengandung berbagai senyawa yang berfungsi menghambat berbagai macam penyakit dan mengandung berbagai bahan aktif yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan menguatkan imun tubuh. Tanaman ini dapat di konsumsi dalam bentuk ekstrak daun dalam bentuk pil, maupun minuman, dan bahan aktif yang di campurkan dalam makanan. Sehingga dapat di simpulkan tanaman kelor sebagai penguat imun tubuh, di masa pandemic covid ini.
Rujukan
[1] B. Mendieta-Araica, E. Spörndly, N. Reyes-Sánchez, F. Salmerón-Miranda, and M. Halling, “Biomass production and chemical composition of Moringa oleifera under different planting densities and levels of nitrogen fertilization,” Agrofor. Syst., vol. 87, no. 1, pp. 81–92, 2013.
[2] Mubasyaroh, Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa. Yogyakarta: Trusmedia Publishing, 2017.
[3] D. Sudarwati, “Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri pada Ekstrak Daun Kelor dan Bunga Rosella,” Indones. J. Chem. Sci., vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016.
[4] F. Anwar, S. Latif, M. Ashraf, and A. H. Gilani, “Moringa oleifera: a food plant with multiple medicinal uses,” Phyther. Res. An Int. J. Devoted to Pharmacol. Toxicol. Eval. Nat. Prod. Deriv., vol. 21, no. 1, pp. 17–25, 2007.
[5] S. S. Toripah, “4. Aktivitas Antioksidan Dan Kandungan Total Fenolik Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera LAM),” Pharmacon, vol. 3, no. 4, 2014.
[6] I. Pratama Putra, A. Dharmayudha, and L. Sudimartini, “Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L) di Bali,” Indones. Med. Veterinus, vol. 5, no. 5, pp. 464–473, 2017.
[7] Ayu Ridaniati Bangun, Siti Aminah, Rudi Anas Hutahaean, and M. Yusuf Ritonga, “Pengaruh Kadar Air, Dosis Dan Lama Pengendapan Koagulan Serbuk Biji Kelor Sebagai Alternatif Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu,” J. Tek. Kim. USU, vol. 2, no. 1, pp. 7–13, 2013, doi: 10.32734/jtk.v2i1.1420.
330 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[8] N. Das Prajapati, S. S. Purohit, A. K. Sharma, and T. Kumar,
“Handbook of medicinal plants: a complete source book. Agrobios.” India), Shyam Printing Press, Jodhpur, 2003.
[9] S. Aminah, T. Ramdhan, and M. Yanis, “Kandungan nutrisi dan sifat fungsional tanaman kelor (Moringa oleifera),” Bul. Pertan. Perkota., vol. 5, no. 2, pp. 35–44, 2015.
[10] D. Yulfianti Yatim, “Influenceof Moringga Leafextracton The Born Baby’sweight And Lengthfrom The Informal Sector Working Pregnant Women,” Gizi FKM, Univ. Hasanudin, I(12), 1-13., vol. 1, no. 12, pp. 1–13, 2018.
[11] W. Isnan and N. M, “Ragam Manfaat Tanaman Kelor ( Moringa oleifera Lamk) Bagi Masyarakat,” Info Tek. EBONI, vol. 14, no. 1, pp. 63–75, 2017.
[12] S. Nasir, D. F. Soraya, D. Pratiwi, J. Teknik, K. Fakultas, and T. Universitas, “Untuk Pembuatan Bahan Bakar Nabati,” J. Tek. Kim., vol. 17, no. 3, pp. 29–34, 2010, doi: 10.1016/j.fct.2012.10.013.
[13] S. Rudianto and S. Alharini, “Studi Pembuatan Dan Analisis Zat Gizi Pada Produk Biskuit Moringa Oleifera Dengan Subtitusi Tepung Daun Kelor,” Progr. Stud. Ilmu Gizi Fak. Kesehat. Masy. Univ. Hasanuddin Makasar, 2013.
[14] L. K. Tanuwijaya, A. P. Gita, I. I. Ummi, A. Ruhana, and others, “Potensi ‘Khimelor’ sebagai Tepung Komposit Tinggi Energi Tinggi Protein Berbasis Pangan Lokal (Health Potential of ‘Khimelor’ as Composite Fluor Having Both High Energy and High Protein Level Based on Local Food),” Indones. J. Hum. Nutr., vol. 3, no. 1, pp. 71–79, 2016.
[15] S. Aritjahja, “Kelor sejuta khasiat. Artikel.” 2017. [16] P. W. Halim, “Kelor sejuta khasiat. Artikel,” 2011, [Online].
Available: https://www.trubus-online.co.id/kelor-sejuta-khasiat/.
[17] T. Estiasih and D. A. Kurniawan, “Aktivitas antioksidan ekstrak umbi akar Gingseng Jawa (Talinum triangulare Willd.),” J. Teknol. dan Ind. Pangan, vol. 17, no. 3, pp. 166–175, 2006.
[18] S. Lenny, “Senyawa flavonoida, fenilpropanoida dan alkaloida.[Karya Ilmiah],” Medan Univ. Sumatera Utara, 2006.
[19] T. D. Sutanto, M. Adfa, and N. Tarigan, “Buah Kelor (Moringa Oleifera Lamk.) Tanaman Ajaib yang dapat digunakan untuk Mengurangi Kadar Ion Logam dalam Air,” J. Gradien, vol. 3, no. 1, pp. 219–221, 2007.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 331
Bab 21
Sirup Daun Jambu Air Sumber Antioksidan Fadjar Kurnia Hartati25
Pengantar
Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tergolong tinggi di dunia sehingga tidaklah berlebihan apabila Indonesia mendapatkan julukan negara mega biodiversitas karena memiliki kawasan hutan tropika basah, termasuk keanekaragaman jenis buah-buahan tropisnya. Bahkan Indonesia merupakan salah satu dari delapan pusat keanekara-gaman genetika tanaman di dunia khususnya untuk buah-buahan tropis seperti jambu air [1], Tanaman jambu air mampu tumbuh dihampir semua tempat di Indonesia karena jambu air termasuk salah satu tanaman yang tidak terlalu sulit dalam pemeliharaannya, sehingga banyak ditanam di pekarangan rumah bahkan tidak jarang juga ditanam di pot. Jenisnya pun sangat beragam, saat ini yang mulai dibudidayakan yaitu jambu madu, jambu citra, jambu king rose, dan jambu local [2]. Keistimewaan lain dari tanaman jambu air adalah buahnya sering bermunculan sepanjang tahun dan sosok tanamannya sangat teduh [3].
Jambu air merupakan salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia, tanaman tropis ini dari genus Syzygium dan family Myrtaceae dan secara botanical diidentifikasi sebagai Syzygium samarangense. Tanaman ini banyak tumbuh juga di Negara-negara Asia Tenggara, kultivar tanaman jambu air (Syzygium samarangense) antara lain kultivar hijau (giant green), merah muda (masam manis pink), dan merah (jambu madu red) [4]. Perhatian masyarakat terhadap tanaman jambu air kebanyakan hanya pada bagian buahnya, sedangkan bagian lain seperti daun dari tanaman ini hampir tidak pernah mendapatkan perhatian. Padahal daun merupakan bagian terbanyak dari tanaman jambu air, yang selama ini paling sering terbuang begitu saja. Pemanfaatan daun jambu air yang sudah dilakukan hanya sebatas sebagai pakan ternak.
Berdasarkan penelitian [5] menunjukan bahwa ekstrak etanol daun jambu air mempunyai aktivitas dalam menghambat enzim yang menghidrolisis karbohidrat seperti α-glukosidase dan α-amilase. Lebih lanjut [6] menjelaskan bahwa daun jambu air mempunyai aktivitas farmakologi sebagai anti oksidan, antikanker, antidiabetes dan anti-
25 Dr. Fadjar Kurnia Hartati Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
332 | New Normal, Kajian Multidisiplin
hiperglikemik. Namun dari sekian banyak penelitian tentang daun jambu air hanya diolah sebagai obat-obatan belum pernah diolah sebagai produk pangan, maka perlu dilakukan pengolahan daun jambu air menjadi produk oalahan yang fungsional sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan bermanfaat pada kesehatan terutama pada kondisi pandemic covid-19 seperti saat ini, selain untuk memanfaatkan daun jambu biji yang selama ini hanya menjadi sampah. Salah satu alternatif olahan daun jambu air yang mudah dan tidak membutuhkan peralatan mahal adalah sirup.
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3544-2013) sirup adalah larutan gula pekat dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Di zaman sekarang ini, industri makanan, minuman, dan suplemen sering menggunakan pemanis baik pemanis alami maupun pemanis sintetis sebagai penambah cita rasa pada produknya. Bahan pemanis alami yang biasa digunakan adalah gula sukrosa atau gula tebu. Sukrosa mempunyai kandungan kalori relatif besar yaitu 346,0 kalori/100 g bahan, tetapi karena gula dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan salah satunya adalah kelebihan kalori, kegemukan, menyebabkan kerusakan pada gigi dan sangat berbahaya bagi penderita diabetes maka penggunaan gula pasir dapat diganti dengan gula yang rendah kalori dan aman untuk kesehatan yaitu gula stevia [7].
Kehadiran gula stevia dapat dijadikan alternatif yang tepat untuk menggantikan kedudukan pemanis buatan atau pemanis sintetis yang memiliki nilai kalori rendah dengan tingkat kemanisan 100-200 kali kemanisan sukrosa dan tidak mempunyai efek karsinogenik yang dapat ditimbulkan oleh pemanis buatan. Rasa manis yang ditimbulkan oleh stevia berasal dari senyawa steviosida yang terdapat pada tanaman stevia, biasanya senyawa tersebut terdapat pada daunnya. Kandungan fitokimia daun stevia terbesar adalah glikosida, steroid dan tannin [7]. Tujuan pemanfaatan daun jambu air menjadi produk pangan antara lain adalah: a. Dapat mengurangi sampah daun jambu air b. Dapat meningkatkan nilai ekonomi daun jambu air c. Dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan ilmu
teknologi pangan melalui keanekaragaman olahan pangan fungsional salah satunya pembuatan sirup daun jambu air dengan menggunakan gula stevia.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 333
d. Memberikan alternatif produk pangan yang menyehatkan dengan memanfaatkan daun jambu air yang melimpah sebagai bahan baku pembuatan sirup daun jambu air.
e. Meningkatkan difersivikasi pangan dengan menambah jumlah jenis produk olahan
f. Berpotensi sebagai salah satu bentuk wirausaha, yang diharapkan dapat membantu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
Pembahasan
Daun Jambu Air
Jambu air termasuk suku jambu-jambuan atau myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Kayu buah jambu air yang keras dan berwarna kemerahan cukup baik sebagai bahan bangunan. Menurut [8], jambu air banyak sekali jenisnya. Jenis jambu air yang banyak ditanam yaitu Syzygium quaeum (jambu air kecil) dan Syzygium samarangense (jambu air besar). Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong atau elips. Warna daun yang muda merah, sedang yang tua hijau. Adapun klasifikasi jambu air menurut [9] adalah sebagai berikut : Kingdom : Plantae Sub Divisi : Spermatophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : Myrtales Famili : Myrtaceae Genus : Syzygium Spesies : Syzygium samarangense
Pohon jambu air memiliki tinggi antara 5-15 m. Batangnya berbengkok-bengkok dan bercabang rendah. Bertangkai pendek dan menebal, panjangnya 3-5 mm, helaian daun berbentuk jorong atau jorong lonjong dengan ukuran 10-25 x 5-12 cm, bertepi tipis, berbintik tembus cahaya, dan berbau aromatis apabila diremas. Bunga berada di ujung ranting (terminal) atau muncul di ketiak daun yang telah gugur (aksial), berisi 3-30 kuntum. Bunga jambu air semarang berwarna kuning keputihan, dengan banyak benang sariyang mudah berguguran. Buahnya bertipe buah buni, seperti lonceng atau buah pir yang melebar dengan lekuk atau alur yang membujur di sisinya, bermahkota kelopak yang melengkung berdaging, besarnya sekitar 3,5-4,5 x 3,5-5,5 cm, kulitnya mengkilap berwarna;
334 | New Normal, Kajian Multidisiplin
merah, kehijauan atau merah hijau kecoklatan. Daging buah putih, memiliki banyak air, dengan bagian dalam seperti spons, aromatic manis atau asam manis [9].
Daun jambu air (Syzygium samarangense) varietas Deli Hijau mengandung senyawa aktif steroid, fenolik, dan triterpenoid. Di masyarakat daun jambu air dapat dimanfaatkan sebagai astringent, demam, menghentikan diare, diabetes, batuk, dan sakit kepala. Bubuk daun jambu dapat digunakan untuk lidah pecah-pecah dan jus daun digunakan dalam mandi dan lotion [11]. Lebih lanjut [6] menjelaskan bahwa daun jambu air mengandung flavonoid, fenolik, dan tannin sebagai antimikroba dan senyawa hexahydroxyflavone, Myricetin, vitamin C, senyawa 2',4'- dihidroksi-6-metoksi-3, 5–dimetilkalkon, senyawa 4-Hidroksibenzaldehid, myricetin-3-O-ramnosid, europetin-3-O-ramnosid, floretin, myrigalon-G dan myrigalon-B yang mempunyai aktivitas farmakologi sebagai anti oksidan, antikanker, antidiabetes dan antihiperglikemik.
Tabel 1 Komposisi Gizi Daun Jambu Air
No Komponen Kadar
1 Vitamin C 5,0 mg
Protein 0,6 g
3 Kalori 46,9 kal
4 Karbohidrat 11,8 mg
5 Lemak 0,2 g
6 Fosfor 9,0 mg
7 Kalsium 7,5 mg
8 Zat besi 1,1 S.I
9 Air 87,0 g
10 Antioksidan 21,14%
Sumber : [10]
Sampai saat ini penggunaan bahan bioaktif dari isolasi bahan alam terus dikembangkan karena sifatnya yang “renewable”, mudah terdekomposisi dan dapat dikeluarkan dari dalam tubuh, sedangkan bahan sintetis dapat menjadi residu yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini menyebabkan senyawa antikanker dari bahan alam banyak dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang berpotensi sebagai antikanker baru dalam strategi pengembangan kemoterapi [12]. Fitokimia adalah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 335
pemeriksaan kandungan kimia untuk mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam suatu tumbuhan, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Dari hasil uji fitokimia diketahui beberapa metabolit sekunder yang ada pada daun jambu air yang berpotensi sebagai antioksidan diantaranya : senyawa flavonoid, tannin, dan vitamin C [12].
Sirup
Sirup merupakan salah satu produk olahan cair yang dikonsumsi sebagian besar orang sebagai minuman pelepas dahaga. Sirup adalah sendiaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa bahan tambahan, bahan pewangi, dan zat aktif sebagai obat [13]. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Sirup mengandung paling sedikit 50% sukrosa dan biasanya 60-65%.
Tabel 2. Syarat Mutu Sirup
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan 1.1 Bau - Normal 1.2 Rasa - Normal 2 Total Gula % Min. 65 (b/b) 3 Cemaran Logam : 3.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 3.2 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 3.3 Timah mg/kg Maks. 40 3.4 Merkuri mg/kg Maks. 0,5 4 Cemaran Arsen mg/kg 5 Cemaran Mikroba 5.1 Angka Impeng Total Koloni/ml Maks. 5 x 102 5.2 Bakteri Caliform APM/ml Maks. 20 5.3 Escherichia coli APM/ml < 3 5.4 Salmonella sp - Negatif/25 5.5 Staphylococcus aureus - Negatif/ml 5.6 Kapang Dan Khamir Koloni/ml Maks. 1 x 102
Sumber : [14] Sirup dapat dibuat dari bahan dasar buah, daun, biji, akar, dan bagian lain dari tumbuhan [15]. Sirup merupakan produk minuman yang dibuat dari campuran air dan gula dengan kadar larutan gula minimal
336 | New Normal, Kajian Multidisiplin
65% dengan atau tanpa bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku SNI 3544 [16] seperti pada Tabel 2 di atas.
Air
Sirup adalah sejenis minuman ringan yang berupa larutan kental dengan cita rasa beraneka ragam. Sirup penggunaannya tidak langsung diminum tetapi harus diencerkan terlebih dahulu. Bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan sirup secara sederhana adalah air dan gula. Air merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan untuk kehidupan manusia, karena air diperlukan untuk bermacam- macam kegiatan seperti minum, pertanian, industri, perikanan, dan rekreasi. Air yang berhubungan dengan hasil-hasil industry pengolahan pangan harus memenuhi setidak-tidaknya standar mutu yang diperlukan untuk minum dan air minum. Tetapi masing-masing bagian dari industri pngolahan pangan mungkin perlu mengembangkan syarat-syarat mutu air khusus untuk mencapai hasil-hasil pengolahan yang memuaskan. Dalam banyak hal diperlukan air yang bermutu lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk keperluan air minum, dimana diperlukan penanganan tambahan supaya semua mikroorganisme yang ada mati, untuk menghilangkan semua bahan-bahan yang ada di dalam air yang mungkin dapat mempengaruhi penampakan, rasa, dan stabilitas hasil akhir, untuk menyesuaikan pH pada tingkat yang diinginkan, dan supaya mutu air sepanjang tahun dapat konsisten [17].
Air dalam pengolahan makanan perlu mendapat perhatian khusus karena berperan besar dalam semua tahapan proses, minimal harus memenuhi syarat mutu air (Tabel 3). Pada tahapan persiapan, air, digunakan untuk merendam, mencuci, dan membersihkan bahan mentah. Pada tahap selanjutnya, air digunakan, antara lain untuk media penghantaran panas selama proses pemasakan, khususnya pada makanan yang diolah dengan teknik pengolahan panas basah, seperti merebus, mengukus, dan mengetim. Air juga digunakan dan berperan sebagai komponen dari masakan, baik sebagai kuah, saus, sirup, serta pada proses gelatinisasi bahan makanan berpati. [19] menambahkan bahwa air juga berperan sebagai media pembersih bagi peralatan, ruangan, maupun orang yang terlibat dalam proses pengolahan makanan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 337
Tabel 3. Syarat Mutu Air No Parameter Satuan Air Mineral Air Dimineral
1 Bau - Tidak berbau Tidak berbau
2 Rasa - Tidak berasa Tidak berasa
3 Warna Unit Pt-Co Maks. 5 Maks. 5
4 Kekeruhan Ntu Maks. 3 Maks. 3
5 pH - 6,0- 8,5 5,0- 7,5
6 Zat Organik mg/l Maks. 10 -
7 Nitrat (NO3) mg/l Maks. 45 -
8 Nitrit (NO2) mg/l Maks. 3 -
9 Ammonium (NH4)
mg/l Maks. 0,15 -
10 Sulfat (S04) mg/l Maks. 200 -
11 Klorida (Cl) mg/l Maks. 250 -
12 Flourida (F) mg/l Maks. 1 -
13 Sianida (SN) mg/l Maks. 0,05 -
14 Besi (Fe) mg/l Maks. 0,1 -
15 Mangan (Mn) mg/l Maks. 0,4 -
16 Klor Bebas (Cl2)
mg/l Maks. 0,1 -
17 Kromium (Cr)
mg/l Maks. 0,005 -
18 Barium (Ba) mg/l Maks. 0,7 -
19 Boron (Br) mg/l Maks. 0,3 -
20 Selenium (Se) mg/l Maks. 0,01 -
21 Timbal (Pb) mg/l Maks. 0,05 Maks. 0,05
22 Tembaga (Cu)
mg/l Maks. 0,5 Maks. 0,5
23 Kadmium (Cd)
mg/l Maks. 0,03 Maks. 0,03
24 Raksa (Hg) mg/l Maks. 0,001 Maks. 0,01
25 Perak (Ag) mg/l - Maks. 0,025
26 Kobalt (Co) mg/l - Maks. 0,01
27 Bakteri E.coli APM/100 ml
< 2 < 2
Sumber : [18] .
338 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Gula
Gula adalah suatu istilah umum yang diartikan bagi setiap karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam industri pangan biasanya digunakan sebagai sukrosa, gula yang diperoleh dari bit atau tebu. Gula bersifat menyempurnakan pada rasa asam dan cita-rasa lainnya dan juga memberikan rasa berisi pada minuman karena memberikan kekentalan [17]. Gula Kristal Putih (GKP) adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfitasi/karbonatasi/ fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi SNI 3140.3:2010 [16]. Syarat mutu Gula Kristal Putih (GKP) dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Syarat Mutu Gula
No Parameter Uji Satuan Persyaratan
GKP 1 GKP 2
1 Warna 1.1 Warna Kristal CT 4,0-7,5 7,6- 10,0 1.2 Warna larutan
(ICUMSA) IU 81-200 201- 300
2 Besar jenis butir Mm 0,8- 1,2 0,8- 1,2 3 Susut pengeringan
(b/b) % Maks. 0,1 Maks. 0,1
4 Polarisasi (oZ,20oC) mg/kg Min. 99,6 Min. 99,5 5 Abu konduktiviti
(b/b) mg/kg Maks. 0,10 Maks. 0,15
6 Bahan tambahan pangan
mg/kg
6.1 Belerang dioksida (SO2)
mg/kg Maks. 30 Maks. 30
7 Cemaran logam mg/kg 7.1 Timbal (Pb) Maks. 2 Maks. 2 7.2 Tembaga (Cu) Maks. 2 Maks. 2 7.3 Arsen (As) Maks. 1 Maks. 1
Sumber: [16]
Carboxyl methyl cellulose (CMC)
Sirup adalah larutan gula pekat dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan yang diijinkan. Pada umumnya sirup yang disimpan mengalami pengendapan sehingga berubah menjadi tidak stabil dan mengakibatkan terjadinya penurunan mutu [20]. Salah satu upaya untuk mempertahankan mutu sirup yaitu dengan penambahan CMC. Carboxyl methyl cellulose (CMC) adalah derivate selulosa yang
New Normal, Kajian Multidisiplin | 339
direaksikan dengan alkalin chloroacetic acid. Struktur karboksil metal selulosa dasar adalah -1,4-Glukopiranosa yang merupakan polimer selulosa. CMC memiliki molekul yang lebih pendek disbanding dengan selulosa murni). CMC digunakan dalam bentuk garam natrium Carboxyl methylcellulose sebagai pemberi bentuk, konsistensi, dan tekstur. CMC berfungsi mempertahankan kestabilan minuman agar partikel padatannya tetap terdispersi merata ke seluruh bagian sehingga tidak mengalami pengendapan [20].
Gula stevia
Daun stevia merupakan tanaman berbentuk perdu (semak), tingginya antara 60-90 cm dengan panjang daun 4-7 cm dan memiliki banyak cabang. Tanaman ini mengandung campuran dari diterpen, triterpen, tannin, stigmasterol, minyak yang muudah menguap dan delapan senyawa manis diterpen glikosida. Taksonomi stevia menurut [21] adalah sebagai berikut:
Sub kingdom : Traecheobionta Super divisi : Spermatophyta Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Sub kelas : Asteridae Ordo : Asterales Famili : Asteraceae Genus : Stevia Spesies : Stevia rebaudiana
Tanaman ini memiliki tingkat kemanisan 200 hingga 300 kali gula
sukrosa [21] . Menurut [22] Stevia memiliki beberapa sifat yaitu : 1) Memiliki kadar kemanisan 100-300 kali dari sukrosa 2) Stabil pada suhu tinggi (100oC), larutan asam maupun basa (range
pH 3-9), dan cahaya 3) Tidak menimbulkan warna gelap pada waktu pemasakan 4) Larut dalam air 5) Tidak larut dalam alkohol murni, kloroform, atau eter 6) Tahan pada pemanasan hingga 200oC
Pemanis dalam tanaman stevia dapat diperoleh dengan proses ekstraksi. Eksraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Proses ekstraksi secara umum dapat dilaku-kan dengan cara maserasi, perkolasi, refluks, ekstraksi dengan alat
340 | New Normal, Kajian Multidisiplin
soxhlet, digesi, dan infusa. Namun ada proses ekstraksi yang dapat mempercepat proses ekstraksi, yaitu dengan cara mengkombinasikan pelarut etanol dibantu dengan gelombang mikro (microwave), yang disebut dengan MAE (Microwave Assisted Exstraction) metode ini memiliki keuntungan yaitu waktu ekstraksi lebih cepat, lebih efisien, serta gelombang mikro yang terdapat di microwave dapat meningkatkan suhu pelarut pada badan, yang dapat menyebabkan dinding pada sel pecah dan zat-zat yang terkandung di dalam sel keluar menuju pelarut, sehingga rendamen yang dihasilkan meningkat [21].
Tabel 5. Komposisi Gizi Daun Stevia (per 100 g bahan)
No Komponen Kadar
1 Energi 270 Kcal 2 Protein 10 g 3 Lemak 3 g 4 Air 7 g 5 Karbohidrat 52 g 6 Abu 11 g 7 Serat kasar 18 g 8 Kalsium 464,4 mg 9 Phosphor 11,4 mg 10 Besi 55,3 mg 11 Sodium 190 mg 12 Potassium 1800 mg 13 Asam oksalik 2295 mg 14 Tannin 0,01 g 15 Steviosida 10- 15 g 16 Rebaudiosida 3- 5 g
Sumber : [23]
Antioksidan
Seperti disebutkan di atas bahwa daun jambu biji mengandung senyawa bioaktif yang mempunyai aktivitas antioksidan. Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam dampak negatif dari adanya radikal bebas. Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang secra umum diketahui sebagai senyawa yang tidak memiliki elektron berpasangan. Secara umum suatu senyawa akan tetap stabil jika elektronnya berpasangan, untuk mencari kestabilannya radikal bebas akan mengambil elektron dari sel lain, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel tersebut dan berimbas
New Normal, Kajian Multidisiplin | 341
pada kinerja sel, jaringan, merusak sistem imunitas tubuh dan pada akhirnya pada proses metabolisme. Radikal bebas bisa berasal dari polusi udara, asap rokok, dan sinar matahari [24]. Jika tubuh memiliki kadar radikal bebas yang lebih tinggi dibandingkan antioksidan maka dapat memicu berbagai penyakit degeneratif. Senyawa yang mampu meng-hambat dan mengikat radikal bebas yaitu antioksidan.
Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dan pembentukan radikal bebas. Selain itu, antioksidan juga berguna untuk mengatur agar tidak terjadi proses oksidasi berkelanjutan didalam tubuh [25]. Pada prinsipnya antioksidan berperan untuk menghentikan reaksi berantai senyawa radikal melalui mekanisme penangkapan radikal bebas yaitu dengan memberikan hidrogen untuk berpasangan dengan elektron bebas dari senyawa radikal menjadi non radikal [26].
Berdasarkan sumbernya antioksidan terbagi menjadi 2 yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari bahan alami atau terkandung dalam bahan alam itu sendiri, seperti yang terdapat dalam bahan pangan rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, biji-biji serealia, buah-buahan dan sayuran, sumber bahan pangan yang kaya akan enzim dan protein. Antioksidan sintetik merupakan antioksidan yang sengaja ditambahkan dalam makanan dan juga memiliki kemampuan untuk menghambat radikal bebas, contoh antioksidan sintetik ialah TBHQ [27].
Uji metode DPPH adalah suatu metode kolorimetri yang efektif dan cepat untuk memperkirakan aktivitas antioksidan. Uji kimia ini secara luas digunakan dalam penelitian produk alami untuk isolasi antioksidan fitokimia dan untuk menguji seberapa besar kapasitas ekstrak dan senyawa murni dalam menyerap radikal bebas..Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas transfer hidrogen sekaligus untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas [28].
Menurut [29] larutan DPPH berperan sebagai radikal bebas yang akan bereaksi dengan senyawa antioksidan sehingga DPPH akan berubah menjadi 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl yang bersifat non radikal. Peningkatan jumlah 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl akan ditandai dengan berubahnya warna ungu tua menjadi warna merah muda atau kuning pucat dan biasa diamati dan dilihat dengan menggunakan spektrofotometer sehingga aktivitas peredaman radikal bebas oleh
342 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sampel dapat ditemukan. Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DDPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi [30]. Keberadaan sebuah antioksidan yang mana dapat menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH [31]. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan bahan pendonor elektron maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan warna ungu akan memudar dan digantikan warna kuning yang berasal dari gugus pikril [32].
Uji Organoleptik
Uji organoleptik adalah pengujian yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap suatu produk, dengan mengandalkan panca indera. Panelis adalah kelompok yang memberikan penilaian terhadap mutu produk. Panelis dibedakan menjadi tujuh yaitu panelis perorangan, panelis terbatas, panelis terlatih (7 – 15 orang), panelis setengah terlatih (15 – 25 orang) dan panelis tidak terlatih (25 orang), panelis konsumen, panelis anak – anak. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam malaksanakan uji organoleptik fisiologi (keadaan fisik panelis), psikologi (perasaan panelis) dan kondisi lingkungan saat pengujian. Dalam pelaksanaanya, digunakan uji hedonik yaitu panelis tidak terlatih diminta memberikan penilaian dalam skala yang menun-jukkan tingkat dari sangat tidak suka sampai sangat suka [33] .
Uji kesukaan pada dasarnya merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan responnya yang berupa senang tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Panelis setengah terlatih digunakan dalam pengujian ini. Panelis diminta untuk mengemukakan pendapat-nya secara spontan tanpa membandingkan dengan sampel standar atau sampel yang diuji sebelumnya. Tipe pengujian ini sering digunakan untuk menilai mutu bahan dan intensitas sifat tertentu, misalnya rasa, aroma, dan warna.
Metode Pembuatan Sirup Daun Jambu Biji
Proses pembuatan sirup daun jambu biji ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan alat dan bahan, tahap pembuatan sirup daun jambu air [34], uji organoleptik dan uji antioksidan. Berikut tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:
New Normal, Kajian Multidisiplin | 343
1. Tahap persiapan alat dan bahan Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu, sirup, ember /
baskom, timbangan duduk dan timbangan analitik, panci, sendok, saringan teh, kompor, pengemas botol harus dalam keadaan bersih sebelum digunakan agar tidak terjadi kontaminasi pada proses percobaan berlangsung. Bahan yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi tiga yaitu bahan pembuatan sirup, daun jambu air, gula stevia, CMC, bahan pendukung yang digunakan adalah air. Tahap pembuatan sirup daun jambu air
2. Tahap pembuatan sirup daun jambu, meliputi beberapa Langkah yaitu a. Sortasi
Daun jambu air dilakukan proses sortasi. Daun jambu air yang akan digunakan sebagai bahan tambahan sirup yaitu daun jambu air yang masih muda yang warnanya hijau muda, sortasi diperlukan untuk menggolongkan bahan pangan sesuai dengan ukuran dan ada tidaknya cacat.
b. Pencucian Pencucian dilakukan dengan air bersih agar buah terbebas dari segala kotoran yang melekat, seperti tanah, debu, sisa pestisida, dan lain- lain. Proses pencucian sebaiknya dilakukan dengan air mengalir supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal yaitu kontaminan dapat lebih diminimalisir.
c. Penimbangan Daun jambu air yang telah di keringkan kemudian daun jambu air ditimbang sesuai dengan kebutuhan yaitu F1 ( 25 gram daun jambu air), F2 ( 50 gram daun jambu air), f3 ( 75 gram daun jambu air).
d. Ekstraksi Perebusan bahan herbal juga disebut ekstraksi. Beberapa metode ekstraksi dengan direbus yaitu infundasi dan dekoksi. Infundasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperature pelarut air harus mencapai suhu 900C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gram maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan infundasi, hanya saja ekstraksi yang dibuat membutuhkan waktu lebih lama (>30 menit) dan suhu
344 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pelarut sama dengan titik didih air dengan menambahkan 65% gula.
e. Penyaringan Setelah dilakukan ekstrasi, langkah selanjutnya adalah proses penyaringan dengan kain saring atau saringan yang halus penyaringan bertujuan untuk memisahkan air sari daun dan serat atau sisa daun sehingga tidak mempengaruhi penampakan produk yang akan dihasilkan nantinya. Penyaringan juga sangat berguna untuk menhasilkan sari yang lebih kecil ukurannya untuk menghindari terjadinya endapan pada sirup yang akan dibuat.
f. Pengemasan Botol dilakukan pencucian terlebih dahulu menggunakan air dengan suhu 88oC. Proses pengisian ke dalam botol dilakukan secara hot filling. Proses pengemasan ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari produk sirup daun jambu air.
Sirup pada umumnya mengandung kadar total gula sebesar minimal 65 %, sedangkan sirup daun jambu air dengan pemanis gula stevia mempunyai kadar total gula 8,25 % dan mempunyai aktivitas antioksidan yang ditunjukkan oleh nilai IC50 sebesar 135,35 ppm, artinya mempunyai aktivitas antioksidan kuat. Dari segi organoleptic, sirup daun jambu biji mempunyai rasa dan aroma dominan gula stevia dan warna hijau kekuningan. Tahapan proses pembuatan sirup daun jambu air dapat dilihat pada Gambar 3.
Penutup
Tanaman jambu air jenisnya sangat beragam, sangat mudah didapat, harganya relatif murah, tidak mengenal musim dan mengan-dung zat gizi yang berguna untuk kesehatan. Selama ini masyarakat hanya memperhatikan pada bagian buahnya saja, padahal bagian daun yang selama ini hanya dibuang saja ternyata mengadung senyawa-senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satu alternatif pemanfaatan daun jambu air menjadi produk pangan adalah sirup, tentunya dengan menggunakan gula yang rendah kalori (yaitu stevia) agar menjadi produk fungsional. Sirup pada umunya mengandung kadar total gula 65 % dan tidak mempunyai aktivitas antioksidan. Adapun sirup daun jambu air yang dihasilkan mengandung kadar total gula yang sangat rendah yaitu 8,25 % dan mempunyai aktivitas antioksidan tergolong kuat.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 345
Gambar 3. Diagram Alir Metode Pembuatan Sirup Dari Daun Jambu Air Sumber: [35]
346 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Rujukan
[1] S. M. Prijono, “Indonesia Negara Mega Biodiversity Dunia,” LIPI, Indonesia.
[2] dan J. T. Muhammad Buhari Sibuea, Muhammad Thamrin, “Kajian Efisiensi Pemasaran Jambu Air King Rose Apple,” J. Agrium, vol. 18, no. 2, pp. 162–168, 2013.
[3] H. M. Hanifa and S. Haryanti, “Morfoanatomi Daun Jambu Air ( Syzygium samarangense ) var . Demak Normal dan Terserang Hama Ulat Morfoanatomy Normal Leaf and Infected Pest Leaf of Water Guava ( Syzygium samarangense ) var . Dem,” Bul. Anat. dan Fisiol., vol. 1, no. 1, pp. 24–29, 2016.
[4] M. M. Khandaker, A. Alebidi, and A. M. Al-saif, “Assesment of Genetic Diversity in Three Cultivars Syzygium samarangense Growth in Malaysia,” Res. J. Biotechnol., vol. 7, no. 3 August, pp. 16–22, 2012.
[5] T. Manaharan, D. Appleton, H. M. Cheng, and U. D. Palanisamy, “Flavonoids Isolated from Syzygium aqueum Leaf Extract as Potential Antihyperglycaemic Agents,” Food Chem., vol. 132, no. 4, pp. 1802–1807, 2012.
[6] P. S. Anggrawati and Z. M. Ramadhania, “Kandungan Senyawa Kimia dan Bioaktivitas dari Jambu Air (Syzygium aqueum Burn. f. Alston),” Farmaka Suplemen, vol. 14, no. 2, pp. 331–344, 2016.
[7] K. Harismah, M. Sarisdiyanti, R. Nurul Fauziyah, J. Ahmad Yani, T. Pos, and P. Kartasura, “Pembuatan Yogurt Susu Sapi Dengan Pemanis Stevia Sebagai Sumber Kalsium Untuk Mencegah Osteoporosis,” J. Teknol. Bahan Alam, vol. 1, no. 1, pp. 29–34, 2017.
[8] K. Prihatman, Bertanam Jambu Air. jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
[9] A. Handaya, “Daya Antimikroba infusum Jambu air Semarang ( Syzygium samarangense ) terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans , In vitro,” Jakarta, 2008.
[10] J. Tandi, “Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Jambu Air (Syzygium aqueum (Burm f.)Alston) Terhadap Glukosa Darah, Ureum dan Kreatinin Tikus Putih (Rattus norvegicus),” J. Trop. Pharm. Chem., vol. 4, no. 2, pp. 43–51, 2017.
[11] S. Nuryani, “Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) Sebagai Antibakteri dan Antifungi,” J. Teknol. Lab., vol. 6, no. 2, p. 41, 2017.
[12] S. Peter, T., Padmavathi, D., Sajini, R.J., and A, “Syzygium
New Normal, Kajian Multidisiplin | 347
Samarangens Review On Morphology, Phytochemistry & Pharmacological Aspects,” Asia J. Biochem. Pharm. Res., vol. 1, no. 2, pp. 155–163, 2011.
[13] H. Ansen, Pengantar Bentuk-Bentuk Sendian Farmasi. Jakarta: universitas Indonesia, 2005.
[14] BSN, SNI 3544:2013 Sirup. Indonesia, 2013, pp. 1–41. [15] H. Margono, T., Detty, S., Sri, Buku Panduan Teknologi Pangan.
Jakarta: LIPI, 2000. [16] BSN, “Gula Kristal Putih (SNI 3140).” Indonesia, 2010. [17] W. Buckle, K.R.A., Edward, G.H., Fleet, M., “Food Scuence.”
DGHE.IDP, Australia, 2013. [18] BSN, Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan. Indonesia, 2006. [19] H. A. Purnawijayanti, Sanitasi Higiene & Keselamatan Kerja Dlm
Pengolh Makanan. Jakarta: Kanisius, 2011. [20] bang P. Ba, “Penambahan CMC (Carboxy Methyl Cellulose) Pada
Pembuatan Minuman Madu Sari Buah Jambu Merah (Psidium guajava) ditinjau dari pH, Viskositas, Total Kapang dan Mutu Organoleptik,” Malang, 2014.
[21] Yulianti, B. Susilo, and R. Yulianingsih, “Influence Of Extraction Time And Ethanol Solvent Concentration To Physical-Chemical Properties Stevia Leaf Extract (Stevia Rebaudiana Bertoni M.) Using Microwave Assisted Extraction Methods,” J. Bioproses Komod. Trop., vol. 2, no. 1, pp. 35–41, 2014.
[22] M. R. dan A. Isnawati, “Kajian: Khasiat Dan Keamanan Stevia Sebagai Pemanis Pengganti Gula,” Media Heal. Res. Dev., vol. 21, no. 4 Des, pp. 145–156, 2012.
[23] L. Buchori, “Pembuatan Gula Non Karsinogenik Non Kalori Dari Daun Stevia,” Reaktor, vol. 11, no. 2, p. 57, 2007.
[24] P. Ramadhan, Mengenal Antioksidan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015. [25] W. Selawa, M. R. J. Runtuwene, and G. Citraningtyas, “Kandungan
Flavonoid dan Kapasitas Antioksidan Total Ekstrak Etanol Daun Binahong [Anredera cordifolia(Ten.)Steenis.],” Pharmacon J. Ilm. Farm. - UNSRAT, vol. 2, no. 01, pp. 18–23, 2013.
[26] P. Rohmatussolihat and S. Si, “Penyelamat Sel-Sel Tubuh Manusia,” BioTrens, vol. 4, no. 1, pp. 5–9, 2009.
[27] N. Fitri, “Butylated Hydroxyanisole Sebagai Bahan Aditif Antioksidan Pada Makanan Dilihat dari Perspektif Kesehatan,” J. Kefarmasian Indones., vol. 4, no. 1, pp. 41–50, 2014.
[28] D. Tristantini, A. Ismawati, B. T. Pradana, and J. Gabriel,
348 | New Normal, Kajian Multidisiplin
“Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung ( Mimusops elengi L ),” in Pengembangan teknologi Kimia Untuk Pengolahan Sumber Daya Indonesia, 2016, p. 2.
[29] R. Y. Kesuma Suyuti, Antioksidan Alami dan Sintetik. Padang: Universitas Andalas, 2015.
[30] D. Pratimasari, “Uji Aktivitas Penangkapan Radikal Buah Carica papaya L. Dengan Metode DPPH,” Surakarta, 2009.
[31] E. Al Ridho, “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Buah Lakum (Cayratia trifolia) Dengan Metode DPPH (2,2-Difenil-1-PikrilHidrazilL),” 2013.
[32] R. Pramesti, “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumput Laut Caulerpa serrulata Dengan Metode DPPH (1,1 difenil 2 pikrilhidrazil),” Akt. Antioksidan Ekstrak Rumput Laut Caulerpa serrulata Dengan Metod. DPPH (1,1 difenil 2 pikrilhidrazil), vol. 2, no. 2, pp. 7–15, 2013.
[33] Susiwi S, Penilaian Organoleptik, no. Ki 531. 2009. [34] N. S. Sri Retna Utami, Yusep Ikrawan, M.ENG., “Kajian
Perbandingan Sari Daun Jambu Biji Dengan Sari Salak Bongkok Dan Penambahan Madu Pada Produk Minuman Fungsional,” Bandung, 2017.
[35] S. Wahyuni, “Sosialisasi Pemanfaatan Jambu Air Menjadi Nata De Syzigium,” Din. J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 4, no. 1, pp. 209–213, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 349
Bab 22
Produksi Hand Sanitizer Di Tengah Kelangkaannya Selama Pandemi Covid-19 Di Lingkungan IAIN Jember A. Suhardi, Laila Khusnah, Laily Yunita Susanti, Rafi’atul Hasanah26
Pengantar
Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organisation (WHO) telah menetapkan Corona Virus Deseas2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini dikarenakan hanya dalam waktu dua minggu saja virus mampu menyebar secara cepat hingga ke wilayah jauh pusat wabah (Tiongkok) dan menginfeksi Negara-negara lain hingga tiga kali lipat [1]. Indonesia merupakan salah satu Negara yang juga mengalami pandemi Corona virus. Adanya pandemi ini diawali dengan temuan dua WNI penderita COVID-19 pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari warga Jepang [2]. Hingga tanggal 31 Maret 2020, tercatat ada 1.528 kasus positif COVID-19 di Indonesia yang tersebar di 31 Provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia [3].
COVID-19 merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2). Gejala klinis yang muncul bermacam-macam, ada yang seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot dan nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat (pneumonia atau sepsis) [4]. Menurut [5], COVID-19 dapat menular dari satu manusia ke manusia lainnya melalui droplet yang dikeluarkan saat batuk/bersin. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui kontak fisik (menyentuh atau berjabat tangan) dengan orang yang terinfeksi serta menyentuh mulut, hidung, mata dengan tangan yang terpapar virus [4].
Adapun cara pencegahan dari COVID-19 ini antara lain dengan melakukan etika batuk dan bersin, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan, menggunakan masker jika memiliki gejala pernapasan, menjaga jarak/physical distancing (minimal 1 meter)dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan serta melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika
26 Dr. A. Suhardi, dkk. Dosen Program Studi Tadris IPA, Institut Agama Islam Negeri,
Jember
350 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor [5]. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah gencar memberikan informasi gejala COVID-19 dan upaya pencegahannya. Informasi tersebut diberitakan melalui berbagai media elektronik maupun media cetak di pinggir jalan maupun fasilitas umum lainnya. Salah satu efek dari informasi tersebut adalah terjadinya kelangkaan hand sanitizer di apotek maupun pertokoan, dan ini terjadi hampir diseluruh kota tidak terkecuali di kota Jember.
Melihat adanya kelangkaan dan mempertimbangkan pentingnya ketersediaan hand sanitizer, maka sebagai ilmuwan dan akademisi Program Studi Tadris IPA terinspirasi untuk memproduksi hand sanitizer sendiri. Hand sanitizer dibuat dengan bahan baku yang mudah diperoleh ditengah keterbatasan ruang gerak selama pandemi. Produksi hand sanitizer ini akan sangat berguna bagi banyak pihak, antara lain masyarakat kampus IAIN Jember baik mahasiswa, dosen maupun karyawan, bahkan masyarakat yang ada di luar kampus. Dengan demikian, kebutuhan hand sanitizer tetap terpenuhi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
Pembahasan
Karakteristik Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit).Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019- nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa [6]. Virus corona merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus Corona tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua sub keluarga berdasarkan serotype dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu alpha coronavirus, betacoronavirus, delta coronavirus dan gamma corona-virus. Corona virus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu dua alphacoronavirus (229E dan NL63), empat betacoronavirus antara lain OC43, HKU1, middle east respiratory syndrome-assosiated coronavirus (MERS-CoV), savare acute respiratory syndrome-assosiated (SARSCoV) dan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV) [7].
Virus corona memiliki struktur khas yang berbeda dengan struktur virus yang lain. Diantaranya memiliki kapsul, partikel
New Normal, Kajian Multidisiplin | 351
berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m.5 Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang.12 Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang [7]. Struktur Viruscorona dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1. Struktur Virus Corona (Sumber: [7]) Seseorang yang terinfekti virus corona akan menunjukan gejala
antara lain gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam dengan suhu >380C, beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru [5]. Selain itu, gejala klinis utama yaitu batuk dan juga diare [7]. Menurut para peneliti dalam jurnal of medicine di New England, virus corona yang keluar melalui droplet saat batuk atau bersin tetap stabil dalam bentuk aerosol selama tiga jam [8]. Sehingga ketika droplet tersebut menempel pada benda, maka kemungkinan besar akan menginfeksi orang yang melakukan kontak dengan benda tersebut. Meskipun virus corona dapat bertahan beberapa jam dalam bentuk
352 | New Normal, Kajian Multidisiplin
aerosol, namun virus corona ini memiliki kelemahan, yaitu sensitive terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh disinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid formalin, oxidizing agent dan kloroform [7].
Oleh karena itu untuk dapat menghindarinya, kementerian kesehatan menyarankan untuk melakukan etika batuk dan bersin, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan, menggunakan masker jika memiliki gejala pernapasan, menjaga jarak/physical distancing (minimal 1 meter) dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan serta melakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangan merupakan hal penting untuk menghindar-kan diri dari penyakit. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencuci tangan sesering mungkin terutama pada saat setelah bepergian atau ketika seseorang akan memakan apapun. Karena tangan merupakan organ yang paling sering bersentuhan dengan banyak benda yang sejatinya benda tersebut seringkali dihinggapi bakteri ataupun virus yang tidak terlihat oleh mata.
Perkembangan Virus Corona
Virus tidak bisa hidup tanpa ada sel inang (host). Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Virus Corona. Pada kasus severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS), merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang terdapat pada kelelawar. Selanjutnya, virus corona dari hewan tersebut dapat berpindah ke manusia atau dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute faces dan oral [7].
Gambar 2. Ilustrasi Transmisi Virus Corona (Sumber: [7])
New Normal, Kajian Multidisiplin | 353
Infeksi Virus Corona biasanya terjadi pada saat musim dingin dan semi. Hal ini berhubungan dengan faktor iklim dan pergerakan populasi yang cenderung mengalami perpindahan. Selain itu, karakter dari virus corona lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat diamati dari dua kejadian munculnya virus yaitu virus SARS di Guangdong pada tahun 2002 dan virus SARS-COV-2 di Wuhan Tiongkok pada bulan Desember 2019. Keduanya terjadi pada musim dingin. virus SARS-COV-2 merupakan jenis baru dari virus corona yang menyebabkan epidemi pertama kali di Wuhan, kemudian oleh WHO diberi nama Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) [7].
Evolusi grup SARS-COV-2 ditemukan pada kelelawar, sehingga diduga host alami SARS-COV-2 adalah kelelawar. Virus Corona tipe baru ini dapat bertransmisi dari kelelawar menuju host perantara kemudian hinggap ke manusia melalui mutasi evolusi. Ada kemungkinan banyak host perantara dari kelelawar ke manusia yang belum dapat diidentifi-kasi. Virus Corona baru, memproduksi variasi antigen baru dan populasi tidak memiliki imunitas terhadap strain mutan virus sehingga dapat menyebabkan pneumonia. Pada kasus ini ditemukan kasus “super-spreader” yaitu dimana virus bermutasi atau beradaptasi di dalam tubuh manusia sehingga memiliki kekuatan transmisi yang sangat kuat dan sangat infeksius [7].
Hand Sanitizer untuk Mencegah Penyebaran COVID-19
Kebersihan merupakan hal penting untuk menghindarkan diri dari penyakit. Pencegahan penyebaran penyakit dapat dilakukan salah satunya dengan mencuci tangan. Tangan kita perlu dicuci sesering mungkin terutama pada saat setelah bepergian atau ketika seseorang akan memakan apapun. Karena tangan merupakan organ yang paling sering bersentuhan dengan banyak benda yang mana benda tersebut seringkali dihinggapi bakteri atuapun virus yang tidak terlihat oleh mata. Mencuci tangan biasanya secara umum dilakukan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, namun ketika kesulitan mendapatkan air maka dapat menggunakan hand sanitizer sebagai pilihan utama. Hal ini dikarenakan hand sanitizer merupakan antiseptik yang baik untuk digunakan sebagai pengganti cuci tangan dengan sabun. Selain itu ditengah kesibukan seseorang dan kepadatan waktu, hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang praktis digunakan serta dapat dibawa kemanapun.
Hand sanitizer dapat dibuat dari bahan alami maupun sintetis. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan hand
354 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sanitizer diantaranya tanaman yang mempunyai potensi untuk meng-hambat pertumbuhan bakteri yang mengandung saponin, flavonoid dan minyak atsiri serta memiliki bau yang khas dan tajam. Tanaman tersebut antara lain daun kemangi (Ocimum basilicum), sere wangi (Cimbopogon nardus), daun jeruk (Citrus hystrix), kulit jeruk (Citrus sp.), daun tembelekan (Lantana camara), daun kemuning (Murraya panniculata L.) Jack, bunga kecombrang (Etlingera elatior), bunga krisan (Chrysantemum sp.) [9]. Hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami memiliki kelebihan yaitu mudah didapatkan di sekitar rumah khususnya di pedesaaan, kemudian memiliki nilai ekonomis karena lebih murah, tidak mengandung bahan kimia berbahaya serta memiliki tingkat keamanan bagi anak-anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Sari dan Isadiartuti [10] yang menyatakan bahwa hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami berupa ekstrak daun sirih (Piper betle Linn) lebih aman dipakai. Bagitupun dengan hand sanitizer yang terbuat dari lidah buaya (Aloe vera) [11].
Hand sanitizer juga dapat dibuat dari bahan sintetis. Bahan sintetis yang sering digunakan adalah alkohol. Penggunaan alkohol telah dilakukan secara luas sebagai obat antiseptik kulit karena mempunyai efek menghambat pertumbuhan bakteri, virus dan jamur [12]. Alkohol yang dapat membunuh kuman secara cepat adalah yang memiliki konsentrasi ±60% sampai 80% [13]. Menurut hasil penelitian Rini, E.P dan Nugraheni, E.R [14] diketahui bahwa antiseptik dengan kadar slkohol 60% sampai 70% tanpa tambahan zat antibakteri lainnya memiliki sifat yang lebih polar sehingga memiliki diameter daya hambat yang lebih besar terhadap bakteri. Alkohol merupakan bahan sintetis yang mudah didapatkan di toko kimia atau apotek. Sehingga alkohol mudah didapat-kan di daerah perkotaan.
Produksi maupun konsumsi hand sanitizer sebaiknya memperha-tikan standar WHO agar aman digunakan. Apabila terjadi kelangkaan hand sanitizer, produksi tetap bisa dilakukan dengan mengikuti standar WHO baik dari segi bahan, prosedur maupun laboratorium tempat produksinya. Dua formulasi berikut direkomendasikan oleh WHO untuk produksi lokal dengan maksimum produksi 50 liter per lot dengan memperhitungkan faktor keamanan dalam produksi dan penyimpanan, serta kendala biaya, dan aktivitas mikrobisida. Untuk formulasi pertama, formulasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan etanol 80%, gliserol 1,45%, hidrogen peroksida (H2O2) 0,125% adalah etanol 96% sebanyak 833,3 mL, H2O2 3%, sebanyak 41,7 mL, Gliserol 98% sebanyak 14,5 ml dan air suling atau akuades. Ketiga bahan kimia tersebut dituangkan ke
New Normal, Kajian Multidisiplin | 355
dalam labu ukur atau gelas ukur 1000 mL. Setelah itu, air suling atau air yang telah direbus ditambahkan ke dalamnya lalu lalu didinginkan. Kocok gelas ukur untuk mencampur semua bahan kimia tersebut. Untuk formulasi kedua, formulasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan isopropil alkohol 75%, gliserol 1,45%, hidrogen peroksida 0,125% antara lain sebagai berikut: Isopropyl alkohol (dengan kemurnian 99,8%) sebanyak 751,5 mL, H2O2 3%, sebanyak 41,7 mL, Gliserol 98% sebanyak 14,5 ml, dan air suling atau akuades. Ketiga bahan kimia tersebut dituangkan ke dalam labu ukur atau gelas ukur 1000 ml, lalu dimasukkan air suling atau air yang telah direbus dan didinginkan. Setelah itu, kocok gelas ukur untuk mencampur semua bahan kimia tersebut [15].
Sosio Kultural Edukasi Mencuci Tangan pada Masyarakat
Pencegahan penyebaran virus maupun bakteri yang paling tepat adalah dengan mencuci tangan. tangan merupakan salah satu pintu masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Data WHO menunjukkan, tangan mengandung bakteri yang jumlahnya 39.000 – 460.000 CFU/cm2 yang berpotensi tinggi menyebabkan penyakit infeksi menular [12]. Mencuci tangan merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam islam, baik sebelum melaksanakan kegiatan ataupun sesudahnya. Misalnya men-cuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur dan bangun tidur begitupun setelah bepergian. Hal ini ditegaskan dalam salah satu hadist nabi yang artinya sebagai berikut:
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum” (HR. Abu Daud no.222, An Nasa’i no.257, dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa’i).
Dari sini dapat diketahui bahwa mencuci tangan sangatlah penting untuk dilakukan, namun pada umumnya mencuci tangan dilakukan hanya pada saat tangan terlihat kotor. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat untuk selalu mencuci tangan, baik sebelum beraktivitas maupun setelah beraktivitas. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengetahui bahwa mencuci tangan tidak hanya dengan menggunakan air dan sabun saja, namun dapat dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan salah satu solusi praktis untuk membersihkan tangan pada saat sibuk atau ketersediaan air terbatas. Sehingga akan mempermudah kita dalam membersihkan tangan. Ketika masyarakat merasa mudah dalam
356 | New Normal, Kajian Multidisiplin
membersihkan tangan maka akan terbentuk kebiasaan dalam mencuci tangan.
Mencuci tangan akan lebih efektif dalam membunuh kuman jika dilakukan dengan benar. WHO menetapkan standar 6 langkah mencuci tangan yang benar (Gambar 3) [16], dengan waktu yang diperlukan yaitu selama 20 detik. Langkah-langkah dalam mencuci tangan yang benar dijelaskan sebagai berikut. Gambar 3. Langkah mencuci tangan yang benar menurut standar WHO (Sumber: [16]) 1) Pertama, letakkan antiseptik pada telapak tangan kemudian usap
dan gosokkan dengan lembut kedua telapak tangan secara memutar 2) Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian 3) Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih 4) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci 5) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 6) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kem udian gosok perlahan
Peran Tadris IPA dalam Penyediaan Hand Sanitizer
Tadris IPA merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Tadris IPA memiliki misi daintaranya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis Teknologi Tepat Guna. Kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis Teknologi Tepat Guna, dan ketiga menyelenggarakan pengabdian masyarakat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 357
dalam bidang pendidikan IPA yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Nusantara dan pengembangan media pembelajaran berbasis Teknologi Tepat Guna.
Tadris IPA merupakan program studi yang memiliki dosen dengan latar belakang keilmuan yang kompeten dibidang science. Diantaranya memliki kompeten dibidang Kimia, Biologi, Fisika. Kompetensi yang dimiliki oleh dosen Tadris IPA sangat mendukung untuk melakukan penelitian dalam pembuatan hand sanitizer yang layak dikonsumsi oleh publik. Berangkat dari misi program studi dan latar belakang dosen tadris IPA tersebut, maka prodi Tadris IPA berusaha untuk memberikan peranan dalam masyarakat ditengah wabah COVID-19 ini dengan membuat hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer ini dilakukan dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan kampus IAIN Jember khususnya dan masyarakat Jember pada umumnya.
Hand sanitizer diproduksi di laboratorium FTIK IAIN Jember. Tim pembuat hand sanitizer terdiri dari 4 orang dosen Tadris IPA dan dibantu dengan beberapa mahasiswa (Gambar 4). Produksi hand sanitizer dilakukan selama 14 hari. Mulai tanggal 19 Maret sampai 04 April 2020. Hand sanitizer diproduksi dari bahan sintetis. Alasan pertama karena bahan tersebut mudah diperoleh, mengingat kampus IAIN Jember berlokasi ditengah kota yang lebih dekat dengan pertokoan. Apalagi transportasi sangat dibatasi terkait adanya lock down dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, bahan sintetis tersebut dapat diperoleh dalam jumlah besar, karena memang selama ini telah terjalin kerjasama yang baik dalam memperlancar kegiatan di laboratorium IAIN Jember.
Gambar 4. Tim dosen yang terlibat dalam pembuatan hand sanitizer (Sumber: Dokumentasi pribadi)
358 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Hand sanitizer yang diproduksi oleh Program Studi Tadris IPA
IAIN Jember yaitu berbentuk spray. Hal tersebut dikarenakan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan hand sanitizer berbentuk gel. Kelebihan hand sanitizer berbentuk spray yaitu tidak menyebabkan kelengketan pada kulit karena cepat kering di tangan [17]. Proses pembuatan hand sanitizer diawali dengan tahap uji coba untuk menemukan formula yang tepat yang disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Ketepatan formula sangat diperlukan untuk menjaga kualitas hand sanitizer yang diproduksi. Uji hand sanitizer dilakukan pada 50 mahasiswa diantaranya pada beberapa mahasiswa yang masih tinggal di Ma’had (Asrama) dan mahasiswa yang berdomisili di sekitar kampus IAIN Jember. Uji coba dilakukan tanggal 20 Maret 2020, dengan cara mendatangkan mahasiswa secara bertahap dari jam 08.00 hingga 16.00. Semua mahasiswa yang bertindak sebagai “tester” hand sanitizer diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil uji tersebut dinyatakan bahwa hand sanitizer yang dihasilkan beraroma segar, mudah menguap dan tidak lengket ditangan serta tidak menyebabkan gatal. Setelah tahap uji coba tersebut, maka hand sanitizer diproduksi dalam jumlah yang besar.
Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi hand sanitizer antara lain labu ukur 1000 ml (1 liter), gelas kimia 100 ml, gelas kimia 1 liter, pipet volume 10 ml dan 15 mL, dan pipet tetes. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian di antaranya etanol 70 %, gliserin 30%, H2O2 50% dan aroma sintesis rasa buah jeruk dan apel. Adapun prosedur pembuatan hand sanitizer dapat dilihat pada gambar 5 dan dijelaskan sebagai berikut. a. Cuci bersih peralatan yang akan digunakan untuk pembuatan hand
sanitizer, b. Ambil 5 mL H2O2 50% dengan pipet volume dan masukkan pada gelas
kimia ukuran 100 mL, c. Tambahkan 20 mL gliserin 30% (dengan menggunakan pipet volume
10 mL) ke dalam gelas kimia yang sudah berisi H2O2 50%, d. Masukkan etanol 70% ke dalam gelas kimia yang sudah berisi
campuran H2O2dan gliserin, tambahkan hingga ukuran 100 mL gelas kimia,
e. Masukkan campuran dalam gelas kimia ke dalam labu ukur ukuran 1000 mL,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 359
f. Tambahkan etanol 70% ke dalam labu ukur hingga mencapai garis batas labu ukur lalu tutup labu ukur dan kocok hingga campuran merata di seluruh labu ukur,
g. Pindahkan larutan hand sanitizer dari labu ukur ke dalam gelas kimia 1 Liter, kemudian tambahkan aroma sintesis rasa buah sebanyak 10 tetes, dan
h. Hand sanitizer siap dikemas ke dalam botol kemasan.
Gambar 5. Proses pembuatan hand sanitizer dan penuangan ke dalam botol berukuran 300 ml (Sumber: Dokumentasi Pribadi).
Hand sanitizer yang telah diproduksi, selanjutnya dikemas dalam botol berukuran 300ml dan 100 ml (Gambar 6). Jumlah hand sanitizer yang dihaslikan sebanyak 1000 botol. Untuk hand sanitizer yang dikemas dalam botol berukuran 100ml, dibagikan kepada seluruh dosen dan karyawan IAIN Jember serta mahasiswa dan masyarakat yang ada disekitar kampus. Sedangkan hand sanitizer yang berukuran 300 ml dibagikan pada setiap unit lembaga yang ada di IAIN Jember dan juga dibagikan kepada takmir masjid yang ada di kabupaten Jember.
Pembagian hand sanitizer tahap pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 Maret 2020. Sebelum pembagian, kampus IAIN Jember mengadakan apel siaga penyebaran COVID-19 dan penyerahan hand sanitizer secara simbolis kepada dekan dan pimpinan lembaga. Adapun masjid yang diberi bantuan hand sanitizer berjumlah 100 masjid yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di kabupaten Jember. Kecamatan yang dimaksud antara lain kecamatan Ajung, jenggawah, Kaliwates, Patrang, Tanggul, Kalisat, Jelbuk, Arjasa dan bangsalsari. Pembagian
360 | New Normal, Kajian Multidisiplin
hand sanitizer pada sejumlah masjid dimaksudkan untuk mensuplei hand sanitizer karena terjadi kelangkaan serta tetap dapat menjaga jamaah masjid dari virus COVID-19.
Gambar 6. Hand sanitizer yang telah di masukkan ke dalam botol berukuran 100 ml (Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Pembagian hand sanitizer tahap kedua dilaksanakan mulai hari kamis sampai sabtu, tanggal 02-04 April 2020. Pengambilan dilakukan secara bartahap oleh seluruh dosen dan karyawan serta mahasiswa yang masih berada di sekitar kampus. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mendatangi laboratorium secara bergantian dan terjadwal. Selain itu, hand sanitizer juga diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kampus IAIN Jember. Pem bagian ini dilakukan oleh tim satgas COVID-19 secara bertahap dan berjalan secara door to door. Pembagian hand sanitizer pada masyarakat juga disertai dengan sosialisasi cara membersihkan tangan yang benar.
Pembagian hand sanitizer pada masyarakat diharapkan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya kebersihan tangan terutama dalam pencegahan virus COVID-19. Karena tangan merupakan salah satu organ tubuh yang paling sering digunakan dan paling banyak bersentuhan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Sehingga tanpa disadari tangan merupakan organ yang paling rentan ditempeli oleh berbagai macam mikroorganisme, seperti virus, bakteri, dan jamur yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain itu, setelah masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan tangan, pembagian hand
New Normal, Kajian Multidisiplin | 361
sanitizer ini diharapkan dapat merangsang terjadinya pembiasaan dalam membersihkan dan mencuci tangan secara rutin dan teratur.
Selain pembagian hand sanitizer, kami juga melakukan sosialisasi dalam penyimpanan dan penggunaan hand sanitizer yang benar. Karena penyimpanan yang kurang tepat dapat mempengaruhi daya bunuh kuman oleh bahan aktif. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bahan aktif dari hand sanitizer ini adalah alkohol 70% yang memiliki karakteristik mudah menguap. Penelitian yang dilakukan oleh Walidah, I. dkk [12] menyatakan bahwa daya bunuh hand sanitizer berbahan aktif alkohol 59% dalam kemasan 50 ml setelah penggunaan berulang-ulang, terjadi penurunan. Pada saat volume 50 ml sampai volume ± 25 ml daya bunuh sebesar 21,38%. Sedangkan daya bunuh kuman pada penggu-naan berulang hand sanitizer dari volume ± 25 ml sampai dengan volume ± 12,5 ml sebesar 15,83%.
Dengan demikian maka masyarakat perlu mengetahui beberapa kriteria yang tepat dalam menyimpan hand sanitizer. Adapun tempat yang aman dalam penyimpanan hand sanitizer adalah tempat yang sejuk dan dijauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar serta menghindari tempat yang dapat mengakibatkan perubahan fisik maupun kimia supaya mutu, khasiat dan kemurniannya terjaga. Selain itu, wadah sebaiknya selalu tertutup dengan baik dan rapat sehingga melindungi isinya terhadap masuknya bahan dari luar yang akan mempengaruhi penguapan, pencairan dan pengangkutan isi. Dianjurkan juga menggunakan wadah tertutup kedap sehingga dapat mencegah menembusnya udara atau gas masuk [12].
Penutup
Covid-19 merupakan virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung maupun droplet. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran dengan cara menjaga kebersihan diri, salah satunya adalah menjaga kebersihan tangan. Oleh karena itu, WHO menyarankan agar tiap individu rutin menjaga kebersihan tangan secara teratur dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, atau menggunakan hand sanitizer. Dari segi kepraktisan, hand sanitizer merupakan antiseptik yang banyak diminati masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, terjadi kelangkaan hand sanitizer dimana-mana termasuk di kabupaten Jember. Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, sebagai pendidik dan ilmuwan tergerak untuk memproduksi hand sanitizer demi menjaga kesehatan bersama, dan
362 | New Normal, Kajian Multidisiplin
mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah kampus, masyarakat sekitar dan masjid yang ada di kabupaten Jember. Selain itu, dengan adanya pembagian hand sanitizer pada masyarakat, Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember berharap agar warga masyarakat memiliki kesadaran untuk membersihkan dan mencuci tangan secara rutin sehingga bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik. Dengan demikian secara bersama-sama dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19.
Rujukan
[1]. Ekarina, “Virus Corona Meluas, WHO Tetapkan sebagai Pandemi Global,” 12 Maret 2020, [Online]. Available: https://katadata.co.id/berita/2020/03/12/virus-corona-meluas-who-tetapkan-sebagai-pandemi-global
[2]. Kompas, “Ini Pengumuman Lengkap Jokowi Soal Dua WNI Positif Corona,” 02 Maret 2020, [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all
[3]. Wikipedia, “Pandemi Koronavirus di Indonesia”, 2020, [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/ wiki/PandemikoronavirusdiIndonesia#Kronologi
[4]. F. Razi, et al. “Bunga Rampai COVID-19: Buku Kesehatan Mandiri untuk Sahabat #Dirumahaja,” Depok: PD Prokami Kota. Maret, 2020. [Online]. Available:http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/lokaciamis/index.php?p=show_detail&id=1823
[5]. Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Desease (COVID-19),” Jakarta: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, [Online]. Available: https://www.persi.or.id/images/2020/data/buku_pneumonia_covid19.pdf
[6]. Unicef, “Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Sekolah”, America: Unicef, WHO dan IFRC. 2020. [Online]. Available:https://www. who.int>docs> searc> indonesia.covid19
[7]. E. Burhan, et al, “Pneumonia COVID-19: Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia,” Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020, [Online]. Available:
New Normal, Kajian Multidisiplin | 363
https://www.persi.or.id/images/2020/data/buku_pneumonia_covid19.pdf
[8]. Kompas, “Virus Corona Dapat Menyebar Di Udara, Ini Penjelasannya”, 19 Maret 2020, [Online]. Available: https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/19/190300623/virus-corona-bisa-menyebar-dari-udara-ini-penjelasannya
[9]. C. Fatimah, and R. Ardiani, “Pembuatan Hand Sanitizer (Pembersih Tangan Tanpa Air) Menggunakan Antiseptik Bahan Alami,” Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, pp. 336-343, 2018, [Online]. Available: https://e-prosiding. umnaw. ac.id> article> download
[10]. R. Sari, and D. Isadiartuti, “Studi Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn.)”, Majalah Farmasi Indonesia, vol. 17 no. 4, pp. 163-169, 2006, [Online]. Available: https://indonesianjpharm.farmasi.ugm.ac.id › view
[11]. D. W. Dewi, S. Khotimah, and D.F Liana, “Pemanfaatan Infusa Lidah Buaya (Aloe Vera) L sebagai Antiseptik Pembersih Tangan terhadap Jumlah Koloni Kuman,” Jurnal Cerebellum, vol.2, no.3, pp.577-589, 2016, [Online]. Available: https://media.neliti .com/media/ publications/ 189002-ID-pemanfaatan-infusa-lidah-buaya-aloe-vera.pdf
[12]. I. Walidah, B. Supriyanta, and Sujono, “Daya Bunuh Hand Sanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59% Dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang Terhadap Angka Lempeng Total (ALT)”, Jurnal Teknologi Laboratorium, vol. 3, no. 1, 2014, [Online]. Available: https://www. teknolabjournal. com>article>download
[13]. A. Asngad, A. Bagas. R, and Nopitasari, “Kualitas Gel Pembersih Tangan (Hand sanitizer) dari Ekstrak Batang Pisang dengan Penambahan Alkohol, Triklosan, dan Gliserin yang Berbeda Dosisnya,” Bioeksperime,vol.4, no.2, pp.61-70, 2018, [Online]. Available: http://jurnal.ums.ac.id> bioekspe rimen>article>download
[14]. E.P.Rini, dan E.R. Nugraheni, “Uji Daya Hambat Berbagai Merk Hand Sanitizer Gel Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escercia coli dan Staphylococcus aureus”, Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research, 01, 18-26, 2018, doi: 10.20961/jpscr.v3i1.15380 [Online]. Available: https://www.researchgate. net/ publica tion/329157011_Uji_Daya_Hambat_Berbagai_Merek_Hand_Sani
364 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tizer_Gel_Terhadap_Pertumbuhan_Bakteri_Escherichia_coli_dan_Staphylococcus_aureus/link/5bf8c1d0458515a69e3752e2/download
[15]. D.A. Putri, “Hand Sanitizer: Manfaat, Penggunaan, Cara Membuat. PT Media Kesehatan Indonesia”. 2020. [Online]. Available:https://doktersehat.com/hand-sanitizer/
[16] Kementerian Kesehatan RI, “Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun di Indonesia Infodatin”, Jakarta Selatan: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014, [Online]. Available: https:// www.kemkes.go.id>download>infodatin-ctps.
[17]. C. Martono, dan I. Suharyani, “Formulasi Sediaan Spray Gel Antiseptik dari Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe Vera)”, Jurnal Farmasi Muhammadiyah Kuningan, vol. 3 no. 1, pp. 29-37, 2018. [Online]. Available: https:// Ojs.stikes-muhammadiyahku.ac. id>article>download
New Normal, Kajian Multidisiplin | 365
Bab 23
Food Estate: Mewujudkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Sutawi27
Pengantar
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian dan ketahanan pangan. Pada kesehatan, sampai Selasa 1 September 2020 pukul 12.00 WIB akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 177.571 kasus, 128.057 sembuh, dan 7.505 meninggal dunia [1]. Kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working from home), pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan menjaga jarak secara fisik dan sosial (physical and social distancing), serta penutupan wilayah secara terbatas (partial lockdown), telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan menganggu ketahanan pangan (food security).
Pada perekonomian, pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak. Pemerintah memproyeksi peningkatan tingkat pengangguran akibat pandemi bisa mencapai 5,23 juta orang dari sejumlah 6,88 juta pengangguran pada bulan Februari 2020 [2], dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019 [3]. Studi yang dilakukan ekonom Arthur Okun yang disebut Hukum Okun (Okun’s Law) mengindikasikan hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi [4]. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi, karena pengangguran tidak memberikan kontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019 menurun 2,97% pada Triwulan I, kemudian merosot menjadi -5,32 pada Triwulan II 2020 [5]. Dalam ilmu ekonomi, suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Jika ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 pertumbuhannya negatif, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi ekonomi.
Pada ketahanan pangan, pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir berpotensi menimbulkan kerawanan pangan (food
27 Dr. Sutawi, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang.
366 | New Normal, Kajian Multidisiplin
insecurity) bahkan dapat memicu darurat pangan (food emergency). Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka banyak penduduk yang akan menderita kekurangan gizi bahkan kelaparan. Selama pandemi Covid-19 beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit pangan karena berada jauh dari daerah produksi. Saat memimpin rapat terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Kepresidenan Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi menyampaikan bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi, telur ayam defisit di 22 provinsi, minyak goreng cukup untuk 34 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan bawang putih defisit di 31 provinsi [6].
Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan pada masa pandemi dan mewujudkan ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19 adalah pembangunan food estate (lumbung pangan). Presiden Joko Widodo pada 9 Juli 2020 telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab pembangunan food estate seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Penunjukan Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanian, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan sekedar urusan memenuhi kebutuhan pangan penduduk, tetapi juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Pem-bangunan pusat pengembangan tanaman pangan ini diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024. Food estate merupakan langkah antisipasi dini krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperingatkan FAO akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang.
Pembahasan
Kontribusi Pertanian
Sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi dampak negatif Covid-19. Pertama, penyedia lapangan kerja terbanyak. Struktur
New Normal, Kajian Multidisiplin | 367
penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan didominasi oleh pertanian sebesar 27,33 persen, disusul perdagangan 18,81 persen; dan industri pengolahan sebesar 14,96 persen [7]. Jumlah angkatan kerja sektor pertanian pada 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding 2018. Sayangnya, penghasilan pekerja pertanian tergolong rendah. Penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan [8]. Penghasilan yang rendah ini merupakan salah satu penyebab generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani muda berusia di bawah 34 tahun hanya 8,66 persen, sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun 22,09 persen. Jumlah petani muda tersebut menyusut 3,4 persen/tahun, lebih cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5 persen/tahun.
Kedua, sektor pertanian menghasilkan 11 bahan pangan strategis (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng). Indonesia baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur, dan minyak goreng, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor. Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhah domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan minyak goreng masing-masing sebesar 95,86%, 98,48%, 99,98%, 96,75%, 99,90, 99,91%, dan 321,66%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada on-trend beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada on-trend adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak mencukupi [9], [10]. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-masing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi 16,77 persen, gula 67,98 persen, dan bawang putih 95,5 persen dari kebutuhan dalam negeri. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) defisit neraca perdagangan pangan sekitar US$ 6,84 milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 trilyun devisa negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun.
368 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Ketiga, penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. BPS merilis PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II 2020 yang mengalami penurunan sebesar -4,19 persen (q-to-q) dan secara year on year (y-on-y) turun -5,32 persen. Kontraksi pertumbuhan dialami hampir semua lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan 30,84 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02 persen. Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19 persen. Dari sektor penyumbang terbesar PDB nasional, pertanian merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh positif tengah terjadi wabah Covid-19. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada Triwulan-II 2020 (q-to-q) dan bahkan secara y-on-y sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen. Peningkatan ini terjadi di tengah kontraksi pertumbuhan sektor usaha akibat pandemi Covid-19. Penopang utama pertumbuhan PDB sektor pertanian berasal subsektor tanaman pangan yang tumbuh 9,23 persen secara tahunan, kemudian subsektor hortikultura 0,86 persen, subsektor perkebunan meningkat 0,17 persen, sedangkan subsektor peternakan dan jasa pertanian dan perburuan masing-masing sebesar minus 1,83 persen dan 2,36 persen. Pangan menjadi kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB sektor pertanian tidak mengalami kontraksi seperti yang dialami sektor lainnya.
Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan (food availability), keterjangkauan pangan (food accessibility), dan konsumsi pangan (food consumption) [11], [12]. UU No. 18/2012 tentang Pangan mengamatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Ketersediaan Pangan
Ketersediaan pangan berarti kemampuan menyediakan pangan baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan menyusun perkiraan ketersediaan, produksi,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 369
dan kebutuhan pangan pokok strategis periode Maret sampai Agustus 2020 (Tabel 1). Perkiraan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa Covid-19 akan mengakibatkan: (1) penurunan produksi sebesar 5% karena harga sarana produksi mahal dan distribusinya tidak lancar; (2) kebutuhan pangan meningkat 5% karena panic buying dan masyarakat menyetok pangan untuk persediaan; dan (3) realisasi impor turun sebesar 5% karena importasi tidak lancar dan negara produsen membatasi ekspor.
Tabel 1. Prakiraan Ketersediaan, Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis Periode Maret sampai Agustus 2020 (000 ton).
No.
Komoditas
Ketersediaan Prakiraan
Kebutuhan
Surplus/ Defisit
Stok (Feb‘20)
Prakiraan Produksi
Rencana Impor
Jumlah Tersedia
1 Beras 3.513,7 19.756,6 0 23.270,3
15.854,9 7.415,4
2 Jagung 661,1 13.708,3 0 14.369,4
11.063,5 3.305,9
3 Bawang Merah
154,6 711,0 0 865,6 736,5 129,1
4 Bawang Putih 30 52,5 360,0 442,5 311,9 130,6
5 Cabai Besar 0 532,8 0 532,8 533,8 -1,0
6 Cabai Rawit 0 539,6 0 539,6 493,8 45,8
7 Daging Sapi/ Kerbau 14,3 236,4 275,5 526,2 393,8 132,4
8 Daging Ayam 98,6 1.880,9 0 1.979,5
1.822,6 156,9
9 Telur Ayam 27,6 2.422,1 0 2.449,7
2.611,5 -161,8
10 Gula Pasir 386,1 1.955,7 638,9 2.980,7
1.469,6 1.511,1
11 Minyak Goreng
8.244,1 14.391,0 0 22.635,1
4.640,1 17.995,0
Sumber: [13]
Ketersediaan sebelas pangan strategis diperkirakan mencukupi kebutuhan dalam negeri sampai Agustus 2020 bahkan tercatat surplus, kecuali cabai besar dan telur ayam ras. Indonesia telah mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam dan telur, dan minyak goreng, sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor. Pasokan beberapa bahan pangan impor diperkirakan meningkat disebabkan kenaikan permintaan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadhan (24 April–23 Mei) dan Idul Fitri (24-25 Mei), dan potensi disrupsi produksi pangan sebagai dampak dari meluasnya penyebaran Covid-19.
370 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Keterjangkauan Pangan
Keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dikelola melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pada aspek fisik, keterjang-kauan pangan menghadapi masalah distribusi karena penduduk Indonesia tersebar di 17.504 pulau, sedangkan pusat produksi ada di Jawa. Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7% (129.438 km2) dibanding luas daratan Indonesia (1.910.931 km2) merupakan sentra produksi sebelas bahan pangan pokok lebih dari 50%. Beberapa provinsi diperkirakan mengalami defisit bahan pangan karena berada jauh dari daerah produksi. Pada aspek ekonomi, keterjangkauan pangan terkendala masalah fluktuasi harga (Tabel 2). Faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga pada sisi permintaan adalah hari-hari besar keagamaan dan budaya masyarakat, sedangkan pada sisi penawaran adalah harga sarana produksi dan rantai pemasaran. Secara umum, harga pangan cenderung mengalami penurunan karena penurunan permintaan akibat pelaksanaan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk pembatasan pergerakan masyakat dan bisnis terkait makanan (warung, restoran, hotel, dan katering), mulai awal April 2020. Deflasi bahan pangan -0,13% pada April 2020 mengindikasikan adanya penurunan harga akibat penurunan permintaan.
Tabel 2. Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis Maret-Agustus 2020 (Rp/kg)
No. Komoditas Maret April Mei Juni Juli Agustus Rerata
1 Beras 11.850 11.900 11.900 11.850 11.850 11.850 11.867
2 Daging Ayam 32.550 29.250 33.050 38.150 36.100 31.800 33.483
3 Daging Sapi 117.900 118.150 119.100 118.250 118.350 118.400 118.358
4 Telur Ayam 25.800 25.800 24.350 25.450 26.350 26.150
25.650
5 Bawang Merah
38.050 43.500 53.600 52.650 38.200 32.200 43.033
6 Bawang Putih 44.850 42.650 36.100 28.850 23.600 23.850
33.317
7 Cabai Merah 38.400 32.100 30.150 29.650 32.800 33.000
32.683
8 Cabai Rawit 39.600 41.000 34.050 33.250 34.300 34.150
36.058
9 Minyak Goreng
13.750 13.800 13.700 13.600 13.600 13.750 13.700
10 Gula Pasir 16.650 18.250 17.550 16.350 15.100 14.700
16.433
Sumber: [14]
New Normal, Kajian Multidisiplin | 371
Konsumsi Pangan
Konsumsi pangan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin miskin keluarga, semakin besar proporsi pengeluaran untuk makanan [15], [16]. Dalam skala lebih luas, semakin kaya sebuah negara, semakin kecil porsi pengeluaran untuk makanan. Pendapatan penduduk Indonesia tahun 2019 sebesar Rp 59,1 juta atau US$ 4.175/kapita, lebih rendah dibanding pendapatan negara berkembang US$ 5.650 dan negara maju US$ 48.250 per kapita. Pengeluaran bulanan penduduk Indonesia Rp 1.124.717 per kapita, Rp 556,899 (49,51%) digunakan untuk makanan dan Rp 567.818 (50,49%) untuk bukan makanan (Tabel 3) [17]. Pengeluaran pangan tersebut digunakan untuk membeli rokok Rp 65.439, mendekati pengeluaran untuk beras Rp 66.936, dan mengalahkan pengeluaran untuk ikan Rp 43.352, daging Rp 23.006, dan telur dan susu Rp 32.196. Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih menyukai racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada pangan hewani sumber protein hewani yang menyehatkan badan dan mencerdaskan pikiran. Tabel 3. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok
Barang Tahun 2014-2018
No Komoditas Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
I Makanan 388.350 412.462 460.639 527.956 556.899
1 Padi-padian 60.235 66.929 64.566 61.455 66.936
2 Ikan/udang/cumi/ kerang
31.849 32.041 33.620 40.478 43.352
3 Daging 14.980 18.048 20.526 24.987 23.006
4 Telur dan susu 23.923 26.616 28.025 29.357 32.196
5 Makanan minuman jadi 103.762 109.968 133.834 172.600 189.223
6 Rokok dan tembakau
49.102 51.608 63.555 65.586 65.439
7 Lainnya 104.499 107.252 116.513 133.493 136.747
II Bukan makanan 387.682 456.361 485.618 508.540 567.818
Jumlah 776.032 868.823 946.257 1.036.496 1.124.717
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) berupa energi 2.150 kkal/kapita/hari dan protein 57 g/kapita/hari. AKG menunjukkan
372 | New Normal, Kajian Multidisiplin
jumlah kalori dan protein minimum yang diperlukan setiap orang dalam sehari untuk dapat hidup sehat dan aktif. Capaian konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia telah melebihi AKG masing-masing 2.153 kkal/orang/hari dan 62,19 g/orang/hari (Tabel 4). Namun, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indonesia baru mencapai 90,4 dari skor ideal 100. Diketahui penduduk Indonesia kelebihan konsumsi energi dari beras dan kekurangan konsumsi protein hewani. Konsumsi beras mencapai 114,6 kg/orang/tahun. Tingkat konsumsi beras tersebut menjadikan Indonesia negara konsumen beras terbesar di dunia, jauh di atas rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60 kg, dan negara tetangga Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg, serta Jepang 58 kg/orang/tahun. Jika konsumsi beras tersebut dibagi harian, maka orang Indonesia mengonsumsi beras 314 g/orang/hari atau 105 g sekali makan, lebih tinggi daripada standar PPH 275 g/orang/hari. Kelebihan energi ini diduga berkaitan erat dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia. International Diabet Federation (IDF) Atlas 2017 melaporkan jumlah penderita diabetes usia 20-79 tahun mencapai 10,3 juta orang, dan menjadikan Indonesia peringkat keenam di dunia setelah Tiongkok, India, AS, Brazil, dan Meksiko.
Konsumsi protein penduduk Indonesia sebesar 62,19 g/orang/hari, terdiri protein nabati 46,41 g (74,63%) dan hewani 15,78 g (25,37%) yang berasal dari ikan 8,23 g, daging 4,2 g, dan telur dan susu 3,35 g. Konsumsi protein hewani tersebut masih tergolong rendah dan berada di bawah konsumi protein hewani Thailand dan Filipina antara 40-50 g, dan Malaysia dan Brunei Darusalam sekitar 50-60 g. Sesuai pedoman PPH, setiap orang idealnya mengonsumsi pangan hewani 161 g/hari, tetapi baru tercapai 125 g/hari. Rendahnya konsumsi protein hewani tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka prevalensi stunting (balita pendek) di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0–59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi (<-2SD) dari standar median WHO. Kemenkes (2018) memperkirakan ada 37,2 persen anak usia 0-59 bulan atau sekitar 9 juta anak Indonesia dengan kondisi stunting, yang berlanjut sampai usia sekolah 6-18 tahun.
Konsumsi pangan ditentukan oleh banyak faktor, seperti harga pangan, pendapatan rumah tangga, kesukaan konsumen, ketersediaan barang pengganti, porsi pendapatan untuk belanja pangan. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur sensitifitas harga dan pendapatan adalah elastisitas permintaan. Pangan dari tanaman
New Normal, Kajian Multidisiplin | 373
umumnya merupakan barang kebutuhan pokok, sedangkan pangan dari produk peternakan masih tergolong barang mewah. Bagi penduduk Indonesia, daging sapi dan daging ayam masih termasuk barang mewah dengan ciri permintaannya elastis terhadap perubahan harga dan pendapatan penduduk. Elastisitas harga dan elastisitas pendapatan daging sapi dan daging ayam bersifat elastis [18], sedangkan telur inelastis [19]. Ini berarti bahwa jika harga naik 1% atau pendapatan turun 1%, maka permintaan daging sapi dan daging ayam turun lebih dari 1%, dan sebaliknya. Jika harga naik 1% atau pendapatan turun 1%, maka permintaan telur akan turun kurang dari 1%, dan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan negara maju dimana elastisitas harga dan elastisitas pendapatan ketiga komoditas peternakan bersifat inelastis. Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan konsumsi pangan. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, ditambah gangguan rantai pasokan, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Konsumsi produk pertanian diprediksi menurun 8,29% dibanding sebelum wabah Covid-19 [20]. Konsumsi pangan diperkirakan menurun 20% dan daging 30% [21], serta konsumsi bulanan daging ayam turun 0,14 kg dan telur 3,73 butir [22]. Pemerintah mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 110 triliun termasuk program bantuan sembako Rp 200.000,-/KPM untuk rumah tangga dengan kesejahteraan terendah. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Food Estate
Dasar Food Estate
Sedikitnya ada empat latar belakang yang mendasari pembangun-an food estate. Pertama, ancaman kerawanan pangan dunia. PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menyebutkan terdapat 821 juta penduduk dunia tergolong rawan pangan kronis sebelum pandemi Covid-19 [23]. Sejak pandemi Covid-19 bertambah 135 juta penduduk terjerumus rawan pangan akut. Jumlah ini bisa bertambah dua kali lipat selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Tingginya pengangguran, hilangnya pendapatan, dan kenaikan harga pangan menyebabkan akses terhadap pangan bagi sebagian penduduk semakin sulit. Di Indonesia, pemerintah memper-kirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Lembaga Demografi FEB UI (2020) memperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah
374 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tangga terancam miskin akibat Covid-19, dengan asumsi garis kemiskinan Rp 440.000 per kapita per bulan, karena adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan. Menurut Hermanto (2020) penyusutan perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan meningkat 6,9-9,9%.
Kedua, munculnya fenomena feeding frenzy. Feeding frenzy dirumuskan McMahon sebagai situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan harga dalam negeri [24]. Sebaliknya, negara pengimpor menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahon menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.
Ketiga, ketergantungan impor bahan pangan Indonesia cukup tinggi. Impor tujuh komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih mengalami ke-naikan dari 21,7 juta ton pada 2016 menjadi 25,2 juta ton pada 2017. Impor ketujuh komoditas pangan yang jumlahnya masing-masing di atas 200 ribu ton per tahun menyebabkan defisit neraca perdagangan komoditas pangan terus melonjak dari US$ 9,9 juta setara Rp 138,6 triliun (2015), US$ 10,2 juta setara Rp 142,8 triliun (2016), mejadi US$ 10,8 juta dan setara Rp 151,2 triliun (2017).
Keempat, luasnya alih fungsi lahan pertanian. Menurut Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Moeldoko (2020), penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 120 ribu hektare setiap tahun. Berdasarkan pemotretan yang dilakukan oleh BPS, BIG, dan LAPAN luas lahan baku sawah Indonesia menyusut dari 7,75 juta ha pada 2013 menjadi 7,1 juta hektar pada 2019 [25]. Ratusan ribu hektar lahan pertanian produktif tersebut setiap tahun beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana pendidikan, jalan raya, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, dan mall.
Kelayakan Food Estate
Berbagai program swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan produktivitas belum mampu mengkompensasi penu-runan produksi akibat penurunan luas lahan akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian yang mencapai lebih dari 100 ribu ha per tahun. Salah satu terobosan pemerintah untuk perluasan lahan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 375
pangan adalah pengembangan kawasan pangan skala luas yang disebut food estate (lumbung pangan). Food Estate merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia yang bersinergi dengan tujuan pemerintah daerah dalam menciptakan aktivitas perekonomian daerah melalui keterlibatan investor dan masyarakat [26]. Selain mendorong peningkatan produksi pangan juga diharapkan terjadinya penciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal khususnya di pedesaan.
Food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh [27]. Food Estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas (an integrated farming, plantation and livestock zone) [28]. Konsep food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh.
Sebagai tahapan awal Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan meningkatkan produktivitas padi sebesar dua ton. Dari 165 ribu hektare lahan tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahun. Sementara itu 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate
376 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dengan total kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare, pada 2021 seluas 33.335 hektare, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare senilai Rp 497,2 miliar. Kehadiran food estate ini diharapkan menjadi cadangan strategis pangan dalam negeri apabila terjadi krisis dan dapat mensuplai bahan pangan baik hasil tanaman maupun peternakan.
Food Estate bukanlah gagasan baru. Tahun 2007 pemerintah mencanangkan pengembangan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua seluas 1,2 juta hektar. MIFEE direncanakan selesai terbangun selama 25 tahun dan akan terwujud pada tahun 2032 yang terdiri dari pembangunan food estate jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Komoditas pangan yang dikembangkan adalah: padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi. Hasil uji coba diperoleh produksi yang tinggi yaitu padi mencapai 7 ton/ha GKP, kedelai 2 ton/ha, tebu 40 ton/ha dan jagung 5 ton/ha pipilan kering. Pemerintah telah menyusun grand design, dan total investasi MIFEE mencapai Rp 50-60 triliun hingga 2014. Setelah 2014, akan diperoleh produksi masing-masing 2 juta ton beras dan jagung, 0,2 juta ton kedelai, gula 2,5 juta ton, CPO 1 juta ton, dan daging sapi 64 ribu ton per tahun. Produksi tersebut akan merupakan sumbangan nyata dalam meningkat-kan ketahanan pangan nasional [29]. Selain MIFEE, ada 3 lokasi food estate yang dinotifikasi secara nasional yaitu Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas sekitar 0,5 juta hektar, dan Jungkat Agri Kompleks di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat seluas 0,25 juta ha. Studi kelayakan food estate di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seluas seluas 4.482 Ha menghasilkan padi 1.662.261 kg - 20.845.766 kg, menyerap tenaga kerja sebesar 50 HOK per Ha per musim tanam [26].
Meskipun secara teknis dan ekonomis layak dikembangkan, namun proyek-proyek food estate tersebut belum berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala yang kompleks. PLG dihentikan karena teknologi yang dipakai mendapat penolakan dari para penggiat ling-kungan nasional dan internasional, sedangkan lokasi food estate yang lain karena konflik lahan, konflik sosial, ketersediaan infrastruktur agribisnis, dan teknologi hingga isu politik [29]. Proyek food estate di Bulungan dan Merauke telah berdampak pada kerawanan pangan yang dihadapi penduduk lokal. Program yang dilakukan untuk meningkatkan pasokan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 377
pangan nasional realitasnya telah meminggirkan sumber-sumber pangan penduduk lokal yang berdampak pada ancaman kehidupannya. Proses peralihan lahan, rekayasa teknologi dan peminggiran pengetahuan lokal akibat proyek food estate menyebabkan sumber pangan pen-duduk setempat menjadi semakin dikorbankan [30].
Penutup
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 berpotensi berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. BKP Kementan memproyeksikan ketersediaan pangan strategis mencukupi sampai kebutuhan dalam negeri sampai Agustus 2020. FAO memperingatkan krisis pangan akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan pada masa pandemi dan mewujudkan ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19 adalah pembangunan food estate (lumbung pangan). Pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan di Kalimantan Tengah diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.
Rujukan
[1] Gugus-Tugas-Covid-19, “Kesembuhan Total Menjadi 128.057 Kasus,” 2020. https://covid19.go.id/p/berita/kesembuhan-total-menjadi-128057-kasus (accessed Sep. 02, 2020).
[2] W. A. Siallagan, “Redam Kesulitan Ekonomi Akibat COVID-19, Pemerintah Lakukan Upaya Ini,” Kementerian Keuangan, 2020. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/redam-kesulitan-ekonomi-akibat-covid-19-pemerintah-lakukan-upaya-ini/.
[3] M. Fauzia, “Sri Mulyani: Corona Sebabkan Jumlah Penduduk Miskin Per Maret 2020 Naik 1,23 Juta,” Kompas.com, 2020. https://money.kompas.com/read/2020/07/16/093100126/sri-mulyani--corona-sebabkan- jumlah-penduduk-miskin-per-maret-2020-naik-1-23?page=all.
[4] Bank-Indonesia, “Pertumuhan Ekonomi dan Pengangguran (Okun’s Law),” Palembang, 2006. [Online]. Available: https://www.google.com/search?q=okun+law+bank+indonesia&oq=okun+law+bank+indonesia&aqs=chrome..69i57j0l2.7668j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8%0ALaporan.
[5] BPS, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020,” Jakarta, 2020. [Online]. Available:
378 | New Normal, Kajian Multidisiplin
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html.
[6] Humas-Setkab, “Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, 28 April 2020 , di Istana Bogor , Provinsi Jawa Barat,” 2020. https://setkab.go.id/rapat-terbatas-melalui-video-conference-mengenai-lanjutan-pembahasan- antisipasi-kebutuhan-bahan-pokok-28-april-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/.
[7] Kominfo, “Dominasi Sektor Pertanian, Jumlah Orang Bekerja Naik 2,50 Juta,” 2019. https://www.kominfo.go.id/content/detail/22584/dominasi-sektor-pertanian-jumlah-orang-bekerja-naik-250-juta/0/berita.
[8] BPS, “Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Musim Tanam per Hektar Budidaya Tanaman Palawija Menurut Komoditas, 2017,” Jakarta, 2019. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/statictable/2019/04/10/2055/nilai-produksi-dan-biaya-produksi-per-musim-tanam-per-hektar-budidaya-tanaman-padi-sawah-padi-ladang-jagung-dan-kedelai-2017.html.
[9] E. Ariningsih, “Performance of National Beef Self-Sufficiency Policy,” Forum Penelit. Agro Ekon., vol. 32, no. 2, pp. 137–156, 2014, doi: 10.21082/fae.v32n2.2014.137-156.
[10] S. Handayani, A. Fariyanti, and R. Nurmalina, “Swasembada Daging Sapi Analisis Simulasi Ramalan Swasembada Daging Sapi Di Indonesia,” Sosiohumaniora, vol. 18, no. 1, pp. 61–70, 2016, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9358.
[11] R. Saputri, L. A. Lestari, and J. Susilo, “Food Consumption Pattern and Family Food Security in Kampar Regency of Riau Province,” J. Gizi Klin. Indones., vol. 12, no. 3, pp. 123–130, 2016, doi: 10.22146/ijcn.23110.
[12] A. Suryana, “Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses,” Forum Penelit. Agro Ekon., vol. 32, no. 2, pp. 123–135, 2014, doi: 10.21082/fae.v32n2.2014.123-135.
[13] K. Hadiutomo, “Kebijakan Pertanian untuk Menangani Dampak Covid-19,” Bul. Perenc. Pembang. Pertan., vol. 1, no. 2, pp. 18–27, 2020, [Online]. Available: http://perencanaan.setjen.pertanian.go.id/public/upload/file/20200415123744BULETIN-EDISI-KHUSUS.pdf.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 379
[14] PIHPS, “Perkembangan Harga Pangan Berdasarkan Daerah,” Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, 2020. https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/daerah.
[15] K. W. Clements and D. Chen, “Affluence and Food: A Simple Way to Infer Incomes,” Currencies, Commod. Consum., vol. 92, no. 4, pp. 320–377, 2010, doi: 10.1093/ajae/aaq049.
[16] K. W. Clements and J. W. Si, “Engel’s Law, Diet Diversity, and the Quality of Food Consumption,” Am. J. Agric. Econ., vol. 100, no. 1, pp. 1–22, 2018, doi: 10.1093/ajae/aax053.
[17] BPS, “Average Monthly Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs), 2013-2018,” BPS (Statistics Indonesia), 2019. https://www.bps.go.id/statictable/2014/12/18/966/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-barang-rupiah-2013-2016.html.
[18] R. Umaroh and A. Vinantia, “Analysis of Animal Protein Consumption in Indonesia Households,” J. Ekon. dan Pembang. Indones., vol. Special Ed, pp. 22–32, 2018, doi: 10.21002/jepi.v0i0.869.
[19] N. Febrianto and J. A. Putritamara, “Proyeksi Elastisitas Permintaan Telur Ayam Ras Di Malang Raya,” J. Ilmu-Ilmu Peternak., vol. 27, no. 3, pp. 81–87, 2017, doi: 10.21776/ub.jiip.2017.027.02.010.
[20] W. McKibbin and R. Fernando, “The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios,” 2020. doi: 10.2139/ssrn.3547729.
[21] N. Adelayanti, “Covid-19 Pandemic Emerges Complexity of Food Problems,” Universitas Gadjah Mada, 2020. https://ugm.ac.id/en/news/19402-covid-19-pandemic-emerges-complexity-of-food-problems (accessed Jun. 26, 2020).
[22] A. S. Ilman, “Effects of High Food Prices on Non-Cash Food Subsidies (BPNT) in Indonesia. Cases Study in East Nusa Tenggara.,” Jakarta, 2020. doi: 10.35497/300890.
[23] D. Andayani, “PBB Catat Ada 821 Juta Penduduk Dunia Kelaparan di 2018,” detikNews, 2019. https://news.detik.com/internasional/d-4625621/pbb-catat-ada-821-juta-penduduk-dunia-kelaparan-di-2018.
[24] P. McMahon, Feeding Frenzy: The New Politics of Food, Main Adition. London: Profile Books, 2013.
[25] M. Desrianto, “Lahan Pertanian Makin Berkurang, Kementan
380 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Siapkan Langkah Ini,” Kompas.com, no. Selasa, 21 Mei 2019, 2019, [Online]. Available: https://kilaskementerian.kompas.com/kementan/read/2019/05/21/130737126/lahan-pertanian-makin-berkurang-kementan-siapkan-langkah-ini.
[26] Asti, D. S. Priyarsono, and Sahara, “Analisis Biaya Manfaat Program Pembangunan Food Estate Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat,” J. Agribisnis Indones., vol. 4, no. 2, pp. 79–90, 2016, doi: 10.29244/jai.2016.4.2.79-90.
[27] Kementan, “Rencana Pengembangan Food Estate Di Indonesia,” Jakarta, 2010. [Online]. Available: http://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/.
[28] Y. Syaukat, “Kebijakan Pengembangan Food Estate di Merauke Pendahuluan,” Bogor, 2010. [Online]. Available: https://www.ipb.ac.id/event/index/2010/12/seminar-food-estate-di-indonesia/33ac783f578e8cdd74f91cefa0da04ae.
[29] E. Santosa, “Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional,” Risal. Kebijak. Pertan. dan Lingkung., vol. 1, no. 2, pp. 80–85, 2015, doi: 10.20957/jkebijakan.v1i2.10290.
[30] A. B. M. Kamim and R. Altamaha, “Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke,” BHUMI J. Agrar. dan Pertanah., vol. 5, no. 2, pp. 163–179, 2019, doi: 10.31292/jb.v5i2.368.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 383
Bab 24
Senandung Wacana “Mantra Wedha” Sebagai Kearifan Lokal Etnik Jawa: Sebuah Model Alternatif Penangkal Covid-19 Dwi Bambang Putut Setiyadi 28
Pengantar
Saat ini masyarakat di dunia sedang mengalami pandemi virus korona yang lebih dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini menginfeksi paru-paru manusia sehingga orang yang terinfeksi mengalami kesulitan bernafas dan dapat menyebabkan meninggal dunia. Mula-mula virus ini muncul dari Wuhan, Tiongkok. Sebuah studi dari Universitas Harvard menyebutkan bahwa virus telah ada di Wuhan sejak akhir bulan Agustus 2019. Virus jenis baru ini dilaporkan kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019 (Kompas, 2020). Dari waktu itu peningkatan adanya kasus virus corona semakin tinggi. Dari negara tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 11 maret 2020, akhirnya WHO menetapkan sebagai pandemi global. Hal ini menimbulkan kepanikan di masyarakat dengan perilaku yang beraneka macam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Namun, semakin hari tidak tampak adanya tanda-tanda penurunan kasus, justru jumlahnya semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Penyebaran pun semakin mendunia, jumlah negara yang terinfeksi virus tersebut makin bertambah dan meluas. Dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan menyebutkan bahwa terdapat 215 negara yang mengalami pandemi. WHO mencatat jumlah kasus ada 20,4 juta kasus di dunia, sedangkan jumlah kematian mencapai 744.000 jiwa. Di Indonesia yang mengumumkan terjangkitnya infeksi virus pada awal Maret 2020, sampai pertengahan Agustus 2020 telah mencapai lebih dari 137 ribu kasus. Kasus tertinggi mula-mula di Jakarta, kemudian menyusul Jawa Timur.
Upaya mengatasi meningkatnya penyebaran kasus infeksi virus telah dilakukan oleh pemerintah dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar kesehatan di Indonesia maupun dunia. Yang terbaru, pemerintah melalui Bio Farma telah mengimpor vaksin dari 28Dr. Dwi Bambang Putut Setiyadi Dosen Linguistik Program Pascasarjana, Universitas
Widya Dharma Klaten.
384 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Tiongkok yang diharapkan dapat mengatasi virus Covid-19. Namun, vaksin inipun masih melalui ujicoba terlebih dahulu pada relawan, yang hasilnya tidak dapat langsung diketahui. Berbagai upaya di dunia dilakukan oleh negara-negara adidaya. Negara-negara itu melakukan riset untuk menemukan vaksin virus tersebut. Namun sampai bulan Agustus, hampir delapan bulan jika dihitung sejak diumumkan oleh WHO, belum menemukan hasil yang menggembirakan.
Selain dengan mengimpor vaksin, Indonesia juga mengupayakan obat-obat tradisional berbahan empon-empon seperti jahe (terutaman jahe merah), temu lawak, lengkuas, kunyit, kencur, lempuyang, dan sebagainya sebagai upaya penangkal virus. Bahan tradisional itu di Indonesia, khususnya Jawa, sangat melimpah dan mudah tumbuh di berbagai lahan. Di Jawa, bahan tradisional itu telah turun-temurun dipakai sebagai obat atau jamu tradisional yang paling dikenal di masyarakat sebagai penyembuhan penyakit dan juga untuk kesehatan. Upaya lain dengan menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat agar terhindar dari virus korona tersebut. Tidak saja obat berbahan herbal, aneka vitamin, handsanitiser, alkohol, dan sejenisnya sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh diburu di apotek-apotek, sehingga banyak apotek dan toko penyedia obat yang kehabisan stok.
Pandemi diartikan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas [1]. Keadaan demikian di Jawa biasa disebut pageblug. Kata pageblug diartikan akeh sing padha nandhang lelara nular lan akeh raja pati ‘banyak yang menderita sakit menular dan kematian dalam jumlah besar’ [2]. Dalam masyarakat Jawa pageblug telah terjadi sejak zaman Majapahit. Pada masa itu kemajuan teknologi belum sebaik sekarang. Pengobatan dilakukan oleh para ahli pengobatan tradisional. Dalam menghadapi pageblug semacam itu, masyarakat Jawa menghadapinya dengan berbagai upaya, selain obat tradisional. Upaya tersebut sering dikenal dengan nama mantra. Mantra dikenal pada hampir semua suku di Indonesia, tak terkecuali di Jawa.
Dalam tulisan ini dibahas mengenai mantra pengobatan yang digubah Sunan Kalijaga berjudul “Kidung Rumeksa Ing Wengi” [3]–[5] yang juga disebut “Mantra Wedha” (selanjutnya dalam tulisan ini disebut “Mantra Wedha”) [5]. Mantra itu berbentuk tembang yang sering dipakai sebagai sarana pengobatan, penolak wabah penyakit maupun penolak balak, santet, penjahat, dan aneka permasalahan lain. Pada masyarakat sekarang mantra itu dimungkinkan tidak lagi memiliki daya seperti yang terjadi pada masa lampau. Pada waktu itu mantra dianggap memiliki
New Normal, Kajian Multidisiplin | 385
daya gaib [6], [7] yang ditimbulkan dari kata-kata dalam mantra. Daya gaib itu dapat menolak datangnya bencana pada seseorang atau masyarakat. Pada saat ini mantra masih juga dipercaya oleh komunitas yang memang mempercayainya, sedangkan komunitas yang tidak mempercayai telah meniinggalkan dan menggantikannya dengan doa melalui agama yang dianutnya [7].
Bertolak dari hal itu, penulis berpikir, bahwa kekuatan doa dapat membantu mengatasi pandemi Covid-19. Doa sangat tergantung kepada orang yang melaksanakannya. Dalam agama Islam pernah dicontohkan oleh Sunan Kalijaga sebagai orang yang memiliki daya linuwih ‘kemampuan lebih yang dimiliki seseorang’ dalam mengucapkan kata-kata dan tentu saja dalam berdoa. Adakah sekarang pemuka agama yang memiliki kekuatan setingkat dengan Sunan Kalijaga untuk menciptakan doa sekuat apa yang telah diciptakan oleh Sunan Kalijaga dalam menghadapi pandemi? Inilah yang kemudian menjadi pemikiran dan harapan peneliti agar disamping obat, juga dipakai doa sebagai senjata untuk menghadapi virus korona. Tentu saja harus ada sosok yang memimpin doa ini dengan daya linuwih-nya yang tinggi memohon kepada Yang Maha Murah agar virus itu lenyap dari bumi Pertiwi. Hal ini dilakukan karena masyarakat Indonesia adalah makhluk religius yang percaya bahwa pandemi ini merupakan bentuk peringatan kepada manusia agar lebih mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Dengan rangkaian doa diharapkan dapat tercipta kekuatan yang berupa permohonan agar masyarakat terhindar dari pageblug yang semakin hari semakin meningkat yang terinfeksi virus tersebut. Upaya yang bagaimana yang harus dilakukan masyarakat agar pandemi Covid-19 dapat segera teratasi?
Pembahasan
Telah diuraikan dalam pengantar di atas bahwa saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah penyakit yang disebut Covid-19. Upaya menemukan obat telah dilakukan oleh para ahli dalam bidang kedokteran melalui berbagai riset, namun belum menghasilkan obat yang jitu untuk menyembuhkan infeksi virus itu. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan penyakit itu belum ada obatnya sampai sekarang. Selain upaya penemuan obat berbahan kimia maupun obat berbahan baku herbal, masyarakat juga melakukan ritual doa sebagai upaya untuk memohon surutnya wabah virus itu. Doa-doa telah dilantunkan kepada Allah Yang Mahakuasa oleh para pemuka agama bersama umat-umatnya. Faktanya belum ada perubahan yang signifikan terhadap
386 | New Normal, Kajian Multidisiplin
penurunan jumlah kasus infeksi virus itu, khususnya di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat setiap hari, pertambahannya mencapai seribu lebih.
Doa-doa dalam menghadapi penyakit yang bersifat pandemik diyakini juga oleh masyarakat tradisional di berbagai suku di Nusantara sebagai sarana penyembuhan dan penangkal wabah penyakit. Doa-doa itu lebih dikenal dengan mantra. Mantra berasal dari bahasa Sansekerta yang mengandung arti jampi, pesona, atau doa [5], [6]. Perjalanan kata mantra dari Bahasa Sansekerta itu kemudian sampai di Jawa melalui penyebaran agama Hindu dan mempengaruhi bahasa Jawa Kuna dan bahasa daerah di Nusantara, sehingga mantra pun dikenal dalam bahasa Jawa Baru, Sunda, Bali, dan Melayu. Selanjutnya disebutkan pula bahwa mantra banyak dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai rangkaian ritual maupun semacam doa keseharian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian lain yang senada, mantra adalah doa yang berupa kata-kata atau kalimat yang berfungsi untuk mengobati [8]. Dalam konsep bahasa Jawa, istilah mantra diberi makna tetembungan sing dianggo ndonga utawa njapani ‘kata-kata yang dipakai untuk berdoa atau mengobati’ [2]. Dari pengertian itu, di Jawa dikenal adanya japa mantra ‘kata-kata untuk mengobati’ sebagai tradisi lisan untuk penyembuhan [9]. Mantra meng-alami perubahan seiring dengan perkembangan agama, kebudayaan dan kehidupan masyarakat pemakai mantra [10].
Mantra telah dikenal lama dan merupakan kebiasaan hidup yang dipraktikkan di berbagai suku yang ada di Nusantara. Kebiasaan hidup yang berlangsung lama itu menjadikan mantra sebagai sebuah kearifan lokal dalam masyarakat. Masing-masing etnik nusantara memiliki kearifan lokal [11], [12]. Hal ini terjadi pula pada budaya masyarakat yang lain seperti nyanyian, pepatah, sesanti, petuah, semboyan, dan sebagainya [13]. Sewaktu bangsa nusantara belum memiliki budaya menulis, diwujudkan dalam bentuk lisan melalui upacara-upacara tradisional, sastra lisan (seperti dongeng, legenda, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Ahimsa-Putra [14] menyebutkan bahwa sebagian kearian lokal itu tersimpan dalam bahasa dan sastra (lisan dan tertulis) suatu masyarakat. Dalam khasanah bahasa dan sastra Jawa juga dikenal adanya mantra sebagai sarana pengobatan maupun sebagai sarana kehidupan yang lain, serta sebagai pengekspresi seni sastra dan budaya Jawa. Dengan demikian mantra dapat dikatakan sebagai bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh etnik Jawa sebagai bagian dari budaya [15].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 387
Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu telah melaksanakan ritual doa pula dalam menghadapi pandemi yang lebih dikenal dengan pageblug. Dalam melakukan doa, masyarakat mengucapkan doa-doa itu dengan mengucapkan mantra-mantra sebisanya, disamping melalui agama yang dianutnya. Mantra-mantra itu ditembangkan dalam waktu-waktu tertentu, biasanya malam hari, untuk aneka kebutuhan dari menolak wabah penyakit sampai menolak kejahatan dan berbagai permasalahan yang lain. Mantra tumbuh subur sebagai sarana masya-rakat dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka melakukan itu secara perorangan maupun melalui jasa orang lain yang dipercaya memiliki daya linuwih dan yang dianggap pula memiliki kedekatan dengan Yang Mahaagung untuk terkabulnya doa tersebut’. Orang yang memiliki daya linuwih itu sering disebut dhukun, kyai, pawang, atau sebutan lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Mantra juga diucapkan oleh para pemuka agama dalam upaya untuk memohon kepada Tuhan agar terlepas dari masalah yang dihadapinya. Sunan Kalijaga yang merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa menciptakan sebuah mantra yang berupa tembang dalam menghadapi segala permasalahan, termasuk pengobatan. Tokoh yang merupakan salah satu Wali Sanga itu juga menciptakan berbagai seni dan kebudayaan yang dipakai sebagai sarana penyebaran agama, seperti wayang, tembang, gamelan, dan aneka seni dan kebudayaan yang lain. Beliau dalam menyebarkan agama Islam memakai sarana-sarana seni dan budaya dalam masyarakat yang kebanyakan telah menganut agama lain, khususnya Hindu. Sunan Kalijaga berupaya mengawinkan kesenian wayang yang berasal India itu dengan menyisipkan kata-kata yang bernuansa Islam seperti “Jimat Kalima Sada” yang dimiliki tokoh Yudhistira. Selain itu, juga mengawnkan tradisi-tradisi Hindu dan Islam untuk memudahkan para penganut agama Hindu tertarik untuk masuk Islam, misalnya kenduri. Salah satu hasil ciptaannya yang lain berkaitan dengan topik tulisan ini adalah mantra yang berbentuk tembang dengan judul “Mantra Wedha”. Wacana tembang “Mantra Wedha” berbentuk tembang macapat dengan metrum Dhandhanggula. Tembang atau sekar macapat merupa-kan salah satu bentuk sastra jenis puisi Jawa baru yang berbentuk tembang. Dikatakan tembang karena dalam membawakan harus dilagu-kan atau dinyanyikan. Sastra Jawa dibagi ke dalam tiga babakan berdasarkan penggunaan bahasanya, yakni sastra Jawa Kuna, Sastra Jawa Tengahan, dan sastra Jawa Baru [16]. Jenis sastra Jawa terbagi atas prosa,
388 | New Normal, Kajian Multidisiplin
puisi, dan drama. Pada masa Jawa Kuna ada puisi yang dipengaruhi oleh sastra kawya India, yang disebut kakawin yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama tembang gedhe (sekar ageng). Puisi Jawa Tengahan muncul seiring dengan masa kerajaan Majapahit (tahun1400-an), yang memiliki pola persajakan berbeda dengan kakawin. Jenis puisi tersebut kemudian disebut kidung atau tembang (sekar) tengahan. Puisi Jawa baru muncul bersamaan dengan perkembangan agama Islam di Jawa, yaitu setelah runtuhnya Majapahit. Puisi Jawa Baru ini memiliki ciri yang berbeda pula dengan kidung, yang kemudian disebut tembang macapat atau tembang cilik atau sekar alit.
Tembang macapat digubah dalam berbagai metrum, antara lain Mijil, Mas Kumambang, Sinom, Asmaradana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, dan Pocung. Urutan penyebutan itu dapat pula menggambarkan siklus kehidupan manusia dari lahir (Mijil) sampai meninggal dan dipocong (Pocung). Ada perbedaan jumlah metrum atau pupuh tembang macapat antara pakar yang satu dengan yang lain. Ada yang menyebut 9, 10, 11, 14, dan ada pula yang menyebutkan 15 metrum [14]. Dalam tulisan ini cukup disebutkan sebelas mantra yang dianggap popular di kalangan masyarakat. Tembang macapat mulai diciptakan oleh para wali dalam rangka penyebaran agama Islam di Jawa. Dhan-danggula diciptakan oleh Sunan Kalijaga, Sinom dan Asmaradana oleh Sunan Giri, Durma oleh Sunan Bonang, Pangkur oleh Sunan Murya, Pocung oleh Sunan Gunungjati, dan sebagainya [16]. Tembang macapat sebagai genre sastra baru berkembang pada masa kepujanggan dan raja Kasunanan Surakarta. Sebagai contoh karya-karya Ranggawarsita, Raja Pakubuwana, dan Mangkunagara.
Tembang macapat dikategorikan sebagai salah satu jenis atau genre teks atau wacana [14], [17], [18]. Tembang macapat sebagai bentuk wacana puisi, memiliki kekhasan dalam jumlah baris, suku kata, dan bunyi sajak akhirnya yang disebut guru gatra, guru wilangan, dan guru lagu. Setiap metrum atau pupuh tembang memiliki perbedaan ketiga ketentuan itu. Dhandhanggula memiliki guru gatra 10, guru wilangan (10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, dan 7), dan guru lagu (i, a, e, u, i, a, u, a, i, a). Guru gatra adalah jumlah baris dalam setiap bait. Jumlah guru gatra Dhandhanggula adalah 10 baris. Tiap baris jumlah suku katanya sudah ditentukan, yaitu baris pertama sampai baris ke sepuluh berjumlah 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, dan 7. Tiap baris harus berakhir dengan bunyi persajakan seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu dari baris pertama hingga baris ke sepuluh harus berakhir dengan bunyi i, a, e, u, i, a, u, a, i, a.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 389
Sebagai contoh dikutipkan dua bait dari teks “Mantra Wedha” dalam uraian selanjutnya. Tembang macapat merupakan bagian dari banyaknya kebuda-yaan Jawa yang sampai sekarang masih dilestarikan. Setiap tahun masih dilombakan di tingkat SD, khsusnya di Kabupten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dalam Pekan Olah Raga dan Seni. Selain itu, masih ada kesenian yang juga memanfaatkan macapat dalam pemen-tasannya seperti, wayang kulit, kethoprak, karawitan, langgam Jawa, dan sebagainya. Ada banyak cengkok ‘nada lagu’ dalam menlantunkan tembang macapat, ada cengkok Solo, Jogja, Semarang, pesisir, dan seba-gainya. Masing-masing metrum dilantunkan dalam iringan musik gamelan ataupun tanpa iringan gamelan. Itu semua merupakan kekayaan kebudayaan Jawa yang telah ada sejak dahulu. Dalam seni karawitan, langgam Jawa, maupun campur sari, macapat sering dipakai sebagai awal dari sebuah gending atau sebuah lagu.
Senandung Wacana “Mantra Wedha” sebagai Model Pemulihan Pandemi Covid-19
Di Jawa atau pada suku lain, jenis mantra ada bermacam-macam, misalnya mantra untuk penyembuhan atau pengobatan, mantra untuk bercocok tanam [19], mantra untuk selamatan [20], mantra untuk upacara-upacara tradisional, mantra untuk kesaktian, mantra untuk penolak guna-guna atau santet dan sejenisnya, mantra untuk pertujukan seni, mantra untuk pengasihan dan kehidupan asmara, mantra untuk kekuasaan, mantra untuk kejahatan, dan sebagainya. Mantra-mantra itu ada yang berbahasa daerah maupun berbahasa Arab, bahasa Sansekerta, maupun bahasa lain. Pada beberapa suku ada aneka mantra yang dipakai sebagai sarana yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan manusia memiliki mantra-mantra. Dalam koleksi Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta terdapat teks naskah Piwulang Sunan Kalijaga yang berisi 60 mantra dalam bahasa Jawa dan bahasa Arab yang isinya diwasiatkan untuk para raja di Surakarta dan Yogyakarta [8]. Dalam tradisi masyarakat Bali juga ditemukan banyak mantra yang dipakai untuk berbagai keperluan, yang disebut “usada’, termasuk pengobatan [12], [21], [22].
Mantra dalam pembahasan ini difokuskan kepada mantra peng-obatan. Mantra pengobatan dilakukan oleh hampir semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan pengobatan melalui mantra di Jawa telah dilakukan oleh Sakdullah [4] yang menkaji Kidung Mantra Wedha yang berisi berbagai ajaran yang
390 | New Normal, Kajian Multidisiplin
berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, termasuk pengobatan. Penelitian tentang mantra pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Banten berhubungan dengan penyembuhan menggunakan mantra me-lalui ritual doa yang dipimpin oleh seorang yang disebut sesepuh [23]. Mantra pengobatan yang dilakukan di Bali yang disebut “usada” telah diteliti oleh [12], [21], [22], [24] . Di Sumatra Barat juga terdapat naskah-naskah mantra pengobatan (dalam bahasa Minangkabau mantra disebut manto) [25] dan juga di Sumatra Utara dikenal adanya mantra pengobatan [26]. Di Kalimantan juga dilakukan penelitian terhadap mantra sebagai sarana pengobatan, pendidikan, dan pranata sosial [7], [27]–[29]. Mantra pengobatan juga dilakukan oleh suku Kokoda di Papua Barat, yaitu mantra pengobatan segala penyakit, penelitinya adalah Hafid dan Putra [30]. Mantra ini menggunakan bahasa Arab dan bahasa Kokoda. Masih banyak lagi penelitian mantra sebagai sarana pengobatan di daerah-daerah wilayah Nusantara yang telah banyak diteliti.
“Mantra Wedha” karya Sunan Kalijaga merupakan salah satu jenis mantra dalam bentuk tembang macapat dengan metrum Dhan-dhanggula. Berdasarkan observasi terhadap beberapa orang yang mengalami masa mantra ini populer, saat itu banyak masyarakat Jawa yang melantunkan tembang itu. Peneliti juga mengalami hal seperti itu ketika ibu peneliti sering menyenandungkan kidung itu pada malam hari. Hal itu dilakukan ketika peneliti sakit. Juga ketika ada rasa takut kalau ada pencuri dan upaya membentengi diri dari kejahatan. Mantra yang berupa kidung ini bisa dikatakan sebagai sebuah doa dalam melakukan permohonan kepada Sang pencipta untuk terhindar dari sakit atau wabah penyakit yang sedang berjangkit. Permohonan doa kepada Yang Maha Penyayang secara sungguh-sungguh, khusuk, dan dengan hati yang bersih dapat menjadikan sebuah permohonan dikabulkan. “Mantra Wedha” yang terdiri dari beberapa pupuh ini juga berisi tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan apek-aspek kehidup-an manusia. Dalam uraian berikut ini, hanya dibahas dua bait dari kidung itu, khususnya yang menyangkut pengobatan. Untuk mengetahui isinya secara lebih mendalam. Berikut ini bait yang pertama dideskripsikan menggunakan transkripsi fonemis.
Dari telaah isi dapat diketahui bahwa isi dari kidung bait pertama itu mengenai sebuah kidung (mantra atau doa) yang menjaga seseorang atau keluarga atau juga masyarakat sepanjang malam (1). Larik ini memiliki implikatur bahwa jika berdoa pada malam hari dengan sungguh-sungguh maka kemungkinan permohonan seseorang akan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 391
terkabul. Ada harapan terhindar dari penyakit dan mara bahaya, bencana, atau wabah yang melanda (2-3). Jim dan setan pun tidak punya kekuatan membantu seseorang untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, juga bencana yang disebabkan oleh api dan air menyingkir (4-10).
Dhandhanggula Gur- Gurun Guru
(1) [OnO kidUȠ ruměksO iȠ wěȠi] ‘ada sebuah kidung yang menjaga malam’
1 10 i
(2) [těgUh ayu luputO ing lOrO] ‘kuat sentosa tidak terkena sakit’
2 10 a
(3) [luputO bilahi kabεh] ‘lepaslah dari segala mara bahaya’
3 8 e
(4) [jIm setan datan purUn] ‘jim dan setan tidak akan mengganggu’
4 7 u
(5) [paněluhan tan OnO wani] ‘yang menenung tidak ada yang berani’
5 9 i
(6) [miwah paȠgawe OlO] ‘serta yang akan berbuat jahat’
6 7 a
(7) [gunane wOȠ lupUt] ‘guna-guna yang dikirimkan sirna’
7 6 u
(8) [gěni atěmahan tIrtO] ‘api dan juga air’
8 8 a
(9) [malIȠ adOh tan OnO Ƞarah mrIȠ mami] ‘pencuri dijauhkan dan tidak ada yang berniat mencuri kepadaku’
9 12 i
(10) [gunO dudU? pan sIrnO] ‘guna-guna yang diarahkan sirna’
10 7 a
Pada bait atau pupuh kedua di bawah ini berisi tentang
permohonan agar semua penyakit kembali ke asalnya (11), semua kuman penyakit menyingkir (12), yang terlihat semua hanya sayang dan rasa belas kasih sesama (13), segala teluh tidak mengenai sasaran atau tidak mempan (14), ibarat kapuk yang jatuh mengenai besi (15), Semua bisa yang dimilki hewan akan luntur jika mengenai manusia (16), begitu pula hewan yang buas pun akan tunduk tidak berdaya, bahkan merasa akrab dan mengasihi manusia (17). Tiada pohon dan tanah yang angker (18). Semua dalam suasana tenteram dan damai di tempatnya masing-masing, landak di lubang tempat tinggalnya, harimau begitu pula (19), serta merak bergembira ria mandi tanah gembur, sebuah tempat yang disukainya (20).
Dalam budaya Jawa banyak kearifan lokal yang berupa ungkapan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia, maupun dengan alam semesta. Begitu pula kidung di atas adalah ekspresi kearifan lokal dari etnik Jawa ketika menghadapi
392 | New Normal, Kajian Multidisiplin
musibah dan bagaimana mengatasinya. Jika seseorang atau masyarakat melakukan permohonan doa dengan tulus lair trusing batin (lahir dan batin) secara ikhlas. Permohonannya keluar dari hati yang paling dalam dan dilakukan secara secara serempak atau bergotong royong atau dalam ungkapan Jawa disebut holopis kontul baris, bersama-sama warga masyarakat, walaupun mungkin dari rumah masing-masing. Disamping itu, juga ada sosok pemimpin agama yang memperkuat permohonan mereka. Sosok pemimpin pada masa itu adalah seorang tokoh agama, wali, yang mumpuni di bidang agama dan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, yang telah ngungkurke kadonyan ‘meninggalkan keduniawian’ dan seorang yang telah mencapai tingkat makrifat. Yang dimohonkan hanyalah memayu hayuning bawana, tata tentrem karta raharja, tansah eling marang Kang Gawe Urip ‘terciptanya keadaan yang aman, tenteram, damai, indah, tenteram, subur alamnya, serta penduduknya selalu Ingat kepada Yang Maha Pencipta ’ yang dalam bahasa Arab keadaan demikian disebut baldatun tayyibatun warobbun ghafur [14]. Dari kondisi yang demikian tentu saja permohonan rakyat memiliki harapan besar untuk dikabulkan.
Pengobatan harus dilakukan secara tata lair lan tata batin ‘tata lahir dan tata batin’. Tata lahir dengan memakai obat yang diproduksi oleh para ahli, sedangkan tata batin dilakukan dengan cara berdoa kepada Yang Mahakuasa karena semua keadaan di dunia tidak bisa lepas dari campur tangan-Nya. Manusia hanya bisa memohon, semua telah ditakdirkan Tuhan. Manungsa hamung sadrema nglakoni ‘manusia hanya sekedar melaksanakan apa yang telah ditakdirkan Tuhan’, kridaning ati ora bisa mbedhah kutaning pasti, budi dayaning menungsa ora bisa ngungkuli garesang Kuwasa ‘tidak setiap keinginan manusia dapat dipenuhi, budi daya manusia tidak bisa melebii kekuasaan atau segala sesuatu yang telah ditakdirkan Tuhan’. Namun demikian, semua umat manusia diwajibkan untuk berusaha, tidak hanya sumarah ‘berserah diri’ saja. Termasuk di dalamnya berupaya keras untuk melindungi diri dari serangan wabah yang melanda. Itu adalah upaya masyarakat Jawa pada masa lampau, pada saat kehidupan Wali sampai dengan masa kemerdekaan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dapatkan semua itu direvitalisasi?.
Sebagai makhuk religius bangsa Indonesia perlu berupaya pula untuk menanggulangi menyebarnya virus korona di Indonesia. Adanya pandemi virus korona menyadarkan kepada manusia di seluruh dunia untuk lebih khusuk lagi dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 393
diri kepada Yang Maha Agung. Adanya kemajuan teknologi sering menyebabkan manusia menjadi lupa, seharusnya tansah eling marang sangkan paraning dumadi ‘selalu ingat akan asal dan tujuan hidupnya’. Manusia disibukkan dan terlena dengan hal-hal yang bersifat keduniawian, sehingga tidak ingat bahwa urip ana sing nguripake ‘hidup ada Yang Memberi Kehidupan’
Dhandhanggula
Guru Gatra/ larik ke
Guru Wilangan
Guru lagu
(11) [sakabεhIȠ lOrO pan samyO bali] ‘semua sakit pergi’
1 10 i
(12) [kεhIȠ OmO pan sami mirudO] ‘segala hama menyingkir’
2 10 a
(13) [wělas asIh pandulune] ‘rasa belas kasih yang dilihat’
3 8 e
(14) [sakεhIȠ brOjO lupUt] ‘segala teluh yang menyerang meleset’
4 7 u
(15) [kadi kapU? tibanIȠ wěsi] ‘ibarat kapuk jatuh di besi’
5 9 i
(16) [sakεhIȠ wisO tOwO] ‘segala bisa tawar’
6 7 a
(17) [sato gala? lulUt] ‘hewan buas jadi jinak’
7 6 u
(18) [kayu aεȠ lěmah saȠar] ‘pohon dan tanah yang angker,’
8 8 a
(19) [sOȠIȠ landa? guwanIȠ moȠ lεmah mirIȠ]
‘tempat tinggal landak dan goa di sebuah lereng tempat tinggal harimau’
9 12 i
(20) [myaȠ pakipOnIȠ měra?] ‘dan sebuah tempat merak mandi tanah gembur’
10 7 a
Tuhan telah memperingatkan manusia dengan menunjukkan
betapa tidak berdayanya manusia menghadapi makhluk yang sangat kecil, yang tidak kasat mata. Semua menjadi tidak berarti dalam keadaan pandemi Covid-19. Teknologi yang dibanggakan manusia, pembangun-an gedung yang mencakar langit, kehebatan manusia mendarat di planet lain, kehebatan manusia menciptakan senjata pemusnah sesama manusia, kecanggihan manusia menciptakan dunia maya, dan sebagai-nya tiada artinya lagi. Mengapa obat penangkal Covid-19 (yang benar-benar bisa nenyembuhkan) belum juga ditemukan sampai sekarang?
Model penanggulangan pandemi dan kejahatan dengan lantunan doa (mantra) seperti yang dilakukan etnik Jawa, kiranya perlu direvitali-
394 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sasi lagi dengan menyesuaikan pada era sekarang. Jika kita masih menggunakan kidung atau mantra mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Saat ini zaman sudah modern, manusia telah memasuki era agama, sehingga sudah selayaknya memakai sarana agama sebagai cara untuk memohon dan memperdalam lagi doa kepada Yang Maha Pemurah untuk memohon agar Covid-19 segera sirna dari bumi Indonesia khususnya [31]. Doa yang dipanjatkan harus dipimpin oleh seorang pemuka agama yang benar-benar ngungkurke kadonyan ‘tidak lagi memikirkan masalah-masalah keduniawian’ dan tanpa pamrih. Pemuka agama dalam hal ini haruslah orang yang benar-benar bersih hatinya dan tanpa pamrih. Yang menjadi pertanyaan, adakah sosok yang didambakan itu di Indonesia? Pastilah ada, hanya jumlahnya mungkin hanya sedikit. Untuk itu, diperlukan refleksi diri semua pemuka agama agar mencapai kedekatan diri dengan Sang Penciptanya. Tujuannya hanya satu, yaitu kondisi baldatun tayyibatun warobbun ghafur. Yang beragama Islam bisa memperdalam amalan-amalan agamanya dengan mencoba menelaah atau mengkaji korelasi nilai-nilai yang terdapat dalam “Mantra Wedha” ini dengan Surat Mu’awwidhatain [3].
Selain itu, secara lahir bangsa Indonesia wajib berupaya mencari dan membuat obat penangkalnya karena betapa banyaknya ahli atau pakar yang telah mencapai pangkat akademik tertinggi atau studi sampai ke jenjang yang paling puncak yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Begitu sulitkah menemukan obatnya? Jangan sampai sulitnya menemukan obat penangkal pandemi berhubungan dengan perhitungan untung-rugi yang cenderung bersifat egois. Jika secara batin bisa memakai model kidung di atas, bagaimana secara lahir? Pasti ada pula para ahli Indonesia yang telah menemukan obat penangkalnya. Masalah yang muncul kemudian adalah kepercayaan kepada seseorang yang telah berhasil menemukan itu jangan sampai terhalang oleh kepentingan pribadi seseorang sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada pihak penemunya. Sebuah tantangan bagi para pakar pengobatan yang telah diakui secara nasional maupun internasional.
Penutup
Pandemi Covid-19 telah mengguncangkan dunia. Semua bangsa yang dilanda pandemi merasa kewalahan menghadapi Si Virus yang mematikan ini. Kondisi ipoleksosbud sangat memprihatinkan. Masyarakat menjadi makhluk yang takut kepada makhluk nano yang sangat sakti itu. Segala cara ditempuh dengan memborong obat-obatan secara masal, baik yang obat kimiawi maupun yang berbahan herbal.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 395
Semua berita yang berhubungan dengan pencegahan infeksi virus diminum secara membabi buta karena takutnya. Keluar rumah pun sampai takut terkena virus tersebut. Aneka obat di toko-toko obat dan apotik kekurangan stok. Para pakar obat dan virus beramai-ramai melakukan penelitian dan uji coba. Hasilnya belum kelihatan menggem-birakan. Semua masih dalam taraf uji coba. Walaupun telah banyak pakar teknologi dan ilmu menciptakan berbagai teknologi dan pengetahuan baru, namun khusus untuk penemuan maupun penciptaan obat Covid-19 belum dapat dilakukan. Itu berdasarkan tata lahir. Jika tata batin perlu kiranya bangsa-bangsa di dunia umumnya, dan khususnya bangsa Indonesia melakukan refleksi diri dengan melakukan permohonan melalui doa yang khusuk dan mendalam (tidak hanya di bibir saja) agar pandemi itu segera sirna. Ada model penolak pandemi yang telah dilaksanakan oleh etnik Jawa masa lampau. Dengan model itu, hendaklah dilakukan permohonan secara sungguh-sungguh dan dipimpin oleh pemuka agama yang benar-benar telah meninggalkan keduniawian dan tanpa pamrih untuk menjadi pemimpin dalam permohonan kepada Yang Maha Pencipta.
Rujukan
[1] K. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kemdikbud, 2019.
[2] Sudaryanto dan Pranowo, Kamus Pepak Basa Jawa. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, 2001.
[3] Z. Nafsiyah and I. H. Ansori, “Kidung Rumeksa ing Wengi dan Korelasinya dengan Surat Mu’awwidhatain (Kajian Living Qur’an),” QOF, vol. 1, no. 2, pp. 143–157, 2017.
[4] M. Sakdullah, “Kidung Rumeksa Ing Wengi karya Sunan Kalijaga dalam Kajian Teologis,” Teologia, vol. 25, no. 2, 2014.
[5] A. Sidiq, “Kidung Rumeksa ing Wengi,” Analisa, vol. XV, no. 01, pp. 127–138, 2008.
[6] Muhammad Hamidin, “Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra Ritual Upacara Kasambu Masyarakat Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna,” J. Bastra (Bahasa dan Sastra), vol. 1, no. 2, 2016.
[7] Jamilah dan F. Ramadania, “Kajian Semiotika Mantra Banjar,” J. Tarb. J. Ilm. Kependidikan, vol. 7, no. 1, pp. 51–57, 2018.
[8] Rahmat, “Piwulang Sunan Kalijaga (Teks Tentang Mantra): Deskripsi Teks dan Akulturasi Bahasa,” Jumantara, vol. 7, no. 1, pp. 89–102, 2016.
396 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[9] Sari; Hawa Intan Malayyana and Widhyasmaramurti, “The
Meaning of Embedded Arabic in Japa - Mantra in Banyakan Village , Kediri , East Java,” in Proceedeings of the International University Symposium on Humanities and Arts ( Inusharta 2019), 2020, vol. 453, no. International University Symposium on Humanities and Arts ( Inusharta 2019), pp. 199–204.
[10] Aswinarko, “Kajian deskriptif wacana mantra,” Deiksis, vol. 5, no. 2, pp. 119–128, 2013.
[11] Marsono, “‘Revitalisasi Kearifan Lokal guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera’ dalam Kemajuan Terkini Riset Universitas Gadjah Mada,” Yogyakarta, 2007.
[12] Mu’jizah, “Naskah Usada sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bali,” Dialektika, vol. 3, no. 2, pp. 191–200, 2016.
[13] N. A. Ridwan, “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal (online),” http://www.nusantara-online.com, 2010. [Online]. Available: http://www.nusantara-online.com.
[14] D. B. P. Setiyadi, Kajian Wacana Tembang Macapat: Struktur, Fungsi, Makna, Sasmita, Sistem Kognisi, dan Kearifan Lokal Etnik Jawa, vol. 1. Yogyakarta, 2012.
[15] K. Saddhono, A. Hartata, and Y. Anis, “Dialektika Islam dalam Mantra sebagai Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa,” Akademika, vol. 21, no. 01, 2016.
[16] K. H. Saputra, Sekar Macapat. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2001.
[17] D. B. P. Setiyadi and A. Setyandari, “Political Discourse: Genre and Figurative Language in the Discourse Debate of the Central Java Governorrs Candidate 2018,” in Proceedings of the International Conference on Language Phenomena in Multimodal Communication (KLUA 2018), 2018.
[18] D. B. P. Setiyadi, “Discourse analysis of Serat Kalatidha: Javanese cognition system and local wisdom,” Asian J. Soc. Sci. Humanit., vol. 2, no. 4, pp. 292–300, 2013.
[19] M. S. Badaruddin, “Linguistic Features as Depicted in Tulembang Mantra,” KnE Soc. Sci., vol. 3, no. 4, p. 609, 2018.
[20] W. Abdullah, “Local Knowledge and Wisdom in the Javanese Salvation of Women Pregnancy lMitonir: An Etholinguistic Perspective,” in Proceeding of 2nd International Conference of Arts Language and Culture, 2018, pp. 172–182.
[21] I. W. Suardiana, “Naskah Pengobatan ‘Usada’ di Bali dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 397
Problematika Pemurnian Teks,” J. Kaji. Bali, vol. 08, no. 02, 2018. [22] I. K. Jirnaya, “Sinkretisme Hindu-Islam dalam Mantra: Sebuah
Kasus dalam Teks Usada Manak,” Addbiyyat, vol. XIV, no. 2Fi, 2015.
[23] D. Fitriani, “Mantra Pengobatan dalam Upacara Penyembuhan terhadap Karakteristik Masyarakat Lebak- Banten,” J. Pendidik. Bhs. dan Sastra Indones., vol. 12, no. 1, pp. 53–58, 2018.
[24] I. B. Suatama, A. A. N. A. Kumbara, and A. A. S. K. Dewi, “Commodification of usada bali: between profit-oriented and negotiation of sasana balian,” Int. J. Soc. Sci. Humanit., vol. 3, no. 2, pp. 136–144, 2019.
[25] D. Suseno, Pramono, and H. N. Hidayat, “Pengobatan Tradisional dalam Naskah-Naskah Minangkabau: Inventarisasi Naskah , Teks dan Analisis Etnomedisin,” Wacana Etn. J. Ilmu Sos. dan Hum., vol. 4, no. 2, pp. 133–152, 2013.
[26] M. Natsir, A. Saragih, S. Sinar, and R. Sibarani, “Mantra for Desease Treatment (Physical) and Its Text Meaning in Tanjung Pura, Langkat, North Sumatra,” Eur. J. English Lang. Lit. Stud., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
[27] I. A. Faisal, “Struktur, Makna, dan Fungsi Mantra Pengobatan Masyarakat Melayu Semitau Kabupaten Kapuas Hulu,” Tuah Talino, vol. 12, no. 1, pp. 29–40, 2018.
[28] F. Fadli et al., “Kajian semiotik mantra pengobatan masyarakat melayu kecamatan matan hilir selatan kabupaten ketapang,” pp. 1–17.
[29] S. N. Triani, L. Yanti, and Kurniawan, “Struktur , Fungsi , dan Makna Mantra Dayak Salako di Desa Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur,” Cakrawala Linguist., vol. 2, no. 2, pp. 89–94, 2019.
[30] A. Hafid and T. Y. Putra, “Konsep Mantra Pengobatan Masyarakat Suku Kokoda dan Manfaatnya Bagi Pendidikan Bahasa,” KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran, vol. 2, no. 2, pp. 129–143, 2019.
[31] Y. Kuswandi, “Doa dalam Tradisi Agama-agama,” Hanafiya J. Stud. Agama-agama, vol. 1, no. 1, pp. 29–33, 2018.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 399
Bab 25
Reformulasi Nilai karakter dalam Pembelajaran Daring di Era Pandemi Untuk Mencegah Fraud Academic Endah Andayani29
Pengantar
Pembelajaran daring menuntut guru mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang dirancang supaya siswa dapat diarahkan ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Salah satu bentuk pembelajaran daring adalah model blended learning, siswa dididik memiliki motivasi belajar mandiri dan memiliki komitmen belajar yang sungguh-sungguh, sekaligus dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran langsung [1]. Pembelajaran online tidak dibatasi ruang dan waktu sejalan dengan protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk memutus rantai resiko penularan [2]; dan pembelajaran online dengan Work From Home (WHF) menjadikan siswa lebih mandiri dan dapat berkreasi [3]. Namun demikian, pandemi Covid-19 berdampak secara langsung pada dunia pendidikan yaitu dapat menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka.
Implementasi pembelajaran daring dalam realitasnya memiliki ketidakefektifan, di antaranya konsep pembelajaran daring masih menjadi kesenjangan di beberapa wilayah terkait akses online, pola kebiasan yang sulit berubah dari metode konvensional menuju online yang membuat siswa mengalami shock untuk beradaptasi dan berpeluang mengambil jalan pintas. Hal ini menjadi faktor penyebab siswa melakukan kecurangan akademik, karena ada tekanan atau target waktu, kesempatan, kebiasaan, kepribadian, kepuasan, keinginan, kebutuhan, ketergantungan pada teman, dan faktor kurangnya percaya diri [4].
Pembelajaran on-line adalah belajar mengubah seseorang menjadi cerdas bukan sekedar pintar. Cerdas dalam hal ini diartikan, siswa berpeluang untuk membuat strategi untuk mengerjakan ujian dan tugas
29 Dr. Endah Andayani, MM, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas
Kanjuruhan Malang
400 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dengan cara copy paste, membuat group untuk menjawab soal secara bersama-sama tanpa melakukan analisis sendiri, adanya kesempatan melakukan penyimpangan diikuti dengan kontrol diri yang rendah dan tidak akan mampu menolak godaan untuk melakukan transaksi akademik sebagai indikasi dari perilaku kecurangan untuk mendapatkan nilai ketuntasan minimal [5], [6]. Hal ini cukup meresahkan di dunia pendidikan, karena siswa menganggap sebuah kelaziman dan jika dibiarkan berlangsung secara terus menerus maka pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang tidak memiliki integritas kepribadian yang baik, sehingga mencetak calon pemimpin bangsa yang tidak berkarakter dan membahayakan suatu bangsa.
Kecurangan akademik sudah banyak dibicarakan oleh para ahli dan kecurangan akademik merupakan suatu permasalahan dalam dunia pendidikan yang bisa terjadi dimana saja [7], banyaknya tindakan kecurangan akademik yang dilakukan di berbagai ranah akademik menunjukkan masih sedikitnya pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dari sisi pembetukan karakter [1]. Cheating merupakan perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat yaitu mendapatkan keberhasilan akademik untuk menghindari kegagalan akademik. Artinya seseorang untuk mencapai keberhasilan dengan cara-cara yang tidak fair (tidak jujur) [8]. Penelitian terkait teori fraud diamond sudah pernah dilakukan dan menemukan bahwa semua variabel yang berada dalam teori fraud diamond yaitu tekanan, kesempatan, rasionali-sasi, dan kemampuan berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan curang di ranah akademik [9].
Fenomena budaya instan yang semua ingin serba praktis menggeser tatanan yang selama ini mampu membentuk karakter. Upaya jalan pintas yang menerobos norma-norma masuk ke berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali di dunia pendidikan, misalnya kecurangan dalam ujian nasional menjadi hal yang lumrah dilakukan di kalangan siswa. Hal tersebut menunjukan turunnya nilai-nilai karakter di kalangan remaja terutama siswa, lebih memprihatinkan lagi adalah sebagian dari siswa yang melakukan kecurangan akademik sudah kehilangan rasa malu dan kemauan untuk memperbaiki diri. Kesalahan tersebut dianggap suatu kesalahan yang “wajar” karena dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan secara bersama sama. Kondisi ini menjadi lebih parah dengan adanya kelenturan dan kemudahan oleh sekolah untuk memudahkan kelulusan, dengan kepentingan menciptakan image sebagai
New Normal, Kajian Multidisiplin | 401
sekolah yang berkualitas, disinyalir telah ikut menyumbang kecurangan akademik di sekolah semakin meluas. Menyadari betapa seriusnya isu mengenai kecurangan akademik dalam dunia pendidikan, maka akan lebih baik untuk dapat ditemukan solusi terhadap masalah kecurangan akademik dengan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Implemen-tasi nilai-nilai karakter yang dimaksud secara konsisten harus dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru, BK, dan Siswa secara bersama-sama mem-budayakan dan membangun karakter di kehidupan sehari-hari dengan sistem pengawasan yang terukur dan diinternalisasikan dalam pem-belajaran.
Berbagai persoalan muncul terkait penyimpangan dan pelang-garan proses akademik yang menghalalkan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas sekolah dan ujian sekolah pada era covid-19 ini, seperti performance siswa ketika penyelenggaraan proses pembelajaran online tidak memiliki standart operating procedure (SOP) yang dibakukan oleh Pemerintah atau sekolah, maka siswa cenderung berinteraksi dan berkomunikasi dengan bebas akan berpengaruh terhadap pola tatanan pola interaksi yang bebas serta tidak mendukung etika yang selama ini sudah terbina di sekolah. Hal-hal inilah yang perlu dibicarakan lebih mendalam, dan dalam paparan ini akan menguraikan reformulasi pembelajaran daring untuk mencegah fraud academic dengan mere-konstruksi nilai-nilai karakter siswa pada kondisi new normal.
Pembahasan
Metode pembelajaran daring harus diarahkan tidak sekadar membuat siswa pintar dari segi intelektual namun juga berkarakter baik, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia bermartabat dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri seseorang supaya dapat berkembang ke arah yang positif. Untuk itu perlu dilakukan reformulasi pembelajaran daring dengan menerapkan monitoring secara periodik dan sistemik dalam proses pelaksanaannya, supaya nilai karakter tetap terbangun dan dapat terhindar dari perilaku penyimpangan akademik. Prinsip implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran daring ini dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif, menyenangkan, dan dapat bertanggungjawab. Pendidikan melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action) yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang kurang menekankan pada aspek penanaman karakter akan menimbulkan berbagai macam
402 | New Normal, Kajian Multidisiplin
permasalahan dikalangan siswa, baik persoalan social, ekonomi, moralitas, kualitas nilai-nilai karakter pada siswa, masih tingginya kecurangan akademik di lingkungan siswa, masih tingginya faktor-faktor pencetus kecurangan akademik, dan implementasi nilai-nilai karakter belum dilakukan secara integratif oleh seluruh civitas akademik apalagi pada era pandemi.
Generasi saat ini merupakan generasi heutagogy di mana dihadapkan pada suatu keadaan yang berubah dengan cepat karena informasi teknologi yang sangat maju dalam hitungan menitnya, dengan demikian penggunaan media sosial dalam pembelajaran daring memberikan kontribusi terhadap keleluasaan waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun [10], siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti classroom, video converence, telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp group. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif [11], dan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran blended learning memiliki hasil belajar lebih baik dibandinhgkan dengan menggunakan pembelajaran langsung [12] .
Pembelajaran daring sebagai dampak covid-19 memberikan relevansi terhadap kurikulum merdeka belajar yang saat ini sedang marak dibicarakan [2]. Pada konsep ini siswa diberikan kesempatan belajar merdeka, dimana guru memberikan pengalaman kontekstual yang lebih luas dan mengarahkan siswa aktif dalam pembelajaran [13]. Pendidik memiliki kewajiban moral untuk mencegah kecurangan, maka pendidik perlu memahami faktor yang diprediksi dapat digunakan untuk menangani virus kecurangan akademik. Langkah yang dilakukan adalah bagaimana pendidik harus memahamkan bahwa tingginya prestasi akademik, akan tetapi diperoleh dengan curang akan menjadi tidak membawa keberkahan dalam hidup siswa, selain itu pendidik perlu menemukan cara untuk membuat siswa menyadari pentingnya memiliki nilai-nilai karakter dan kecakapan hidup yang akan berguna bagi hidup siswa [14]. Nilai komunikatif dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi. Nilai mandiri, kreatif, kerja keras, tanggungjawab, gemar membaca dan jujur dapat diimplementasi pendidik dengan memberikan latihan soal sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggungjawab, gemar membaca materi yang diberikan, kemandirian, kejujuran juga kreatifitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 403
Faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan akademik, dapat dilihat pada aspek individual atau pribadi (suka mencontek teman, mencontek itu adalah sesuatu hal yang biasa); aspek kepribadian (adanya persepsi bahwa dengan mencontek nilai prestasi akademik siswa menjadi baik, dan kebiasaan mencontek teman); aspek teman sebaya (memiliki kelompok dalam melakukan kecurangan akademik dan mengatur strategi melakukan kecurangan sebelum ujian); aspek situasi (mencontek teman ketika mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal dan berusaha mencontek pada saat soal yang dikerjakan sulit); aspek self-efficacy (melakukan kecurangan ketika merasa tidak mampu dalam menyelesaikan pekerjaan dan tidak mampu dalam mengerjakan soal dan melakukan kecurangan akademik ketika tidak menguasai kompetensi); aspek perkembangan moral (tidak akan mencontek karena melanggar tata-tertib, senang mendapatkan prestasi akademik hasil sendiri meskipun tidak memuaskan); dan aspek religi (melakukan kecurangan akademik merupakan perbuatan tidak baik dan merasa bersalah setelah melakukan kecurangan akademik).
Reformulasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran Daring di Era Pandemi Untuk Mencegah Fraud Academic
a. Persepsi siswa tentang prestasi akademik
Prestasi akademik merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk nilai baik pada saat mengerjakan tugas harian ulangan, atau ujian. Mendapatkan prestasi akademik yang baik merupakan hal yang penting, karena dapat membahagiakan orangtua, naik kelas, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan upaya dalam mencari kerja, maka siswa harus selalu berusaha giat belajar secara mandiri, belajar kelompok, mengikuti bimbingan belajar diluar sekolah, selain itu siswa harus melawan rasa malas dalam belajar. Sedangkan siswa yang tidak selalu berusaha untuk mendapatkan prestasi akademik pada semua pelajaran mereka memiliki anggapan: 1) pelajaran yang tidak ikut ujian nasional tidak perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena tidak menentukan kelulusan siswa, 2) tidak semua matapelajaran disukai oleh siswa, 3) siswa tidak yakin akan kemampuannya untuk mendapatkan nilai prestasi akademik yang baik, 4) agar ilmu yang dipelajari tidak sia-sia. Sebagian besar siswa menganggap ujian nasional dan kejuruan merupakan pelajaran yang penting untuk dikuasai. Untuk mendapatkan prestasi akademik ada yang melakukan dengan cara baik dan juga ada
404 | New Normal, Kajian Multidisiplin
yang melakukan dengan cara yang tidak baik, adapun cara yang baik yaitu dengan melakukan: 1) belajar secara mandiri, 2) belajar kelompok, dan 3) mengikuti bimbingan belajar, sedangkan cara yang tidak baik yaitu dengan melakukan: 1) menyalin tugas yang diberikan guru dari hasil pekerjaan teman, 2) meminta bantuan teman untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, 3) mencontek pada teman saat ujian/tes, 4) membuat catatan kecil untuk dicontek pada saat ujian/tes, dan 5) Saling tukar jawaban kepada teman.
Hambatan siswa dalam mencapai prestasi akademik yang baik
Hambatan dalam mendapatkan prestasi akademik yang baik, bagi seorang pelajar merupakan sebuah tantangan tersendiri yang harus diperjuangkan, hambatan untuk mendapatkan prestasi baik yang dialami oleh siswa meliputi: faktor internal adalah: 1) malas belajar, tidak suka pelajaran, kebiasaan mencontek, sulit memahami pelajaran, kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak bisa mengatur waktu belajar dengan baik, dan sering lupa materi yang sudah dipelajari. Sedangkan dari faktor eksternal: teman, lingkungan belajar yang kurang kondusif, game, penggunaan media sosial yang tidak tepat guna, teman yang salah keluarga yang tidak mendukung, tidak ada waktu belajar, guru yang kurang inovatif, dan fasilitas belajar yang kurang memadai(termasuk akses intrenet)..
Siswa paham bahwa tindakan curang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, hal ini karena siswa beralasan: 1) kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dijalankan, 2) hasil yang baik jika didapatkan dari hasil mencontek tidak memberikan kebanggaan bagi siswa, 3) teman yang akan dicontek belum tentu jawabannya benar, 4) akan merusak moral dan karakter siswa, 5) ilmu yang kita dapatkan menjadi tidak bermanfaat, 6) melakukan kecurangan menjadikan siswa tidak pintar.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akademik
Faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kecurangan akademik terdiri dari: 1) individu atau pribadi, 2) kepribadian, 3) teman sebaya, 4) situasi, 5) self efficacy, dan religi. Kecurangan akademik dilaku-kan oleh siswa karena mereka menginginkan nilai yang baik agar bisa naik kelas dan tidak dimarahi oleh orangtua, pada saat mereka mengerjakan soal tidak bisa atau mereka merasa sulit maka mereka akan melakukan beberapa hal berikut ini: 1) menyalin tugas yang diberikan guru dari hasil pekerjaan teman, 2) meminta bantuan teman untuk
New Normal, Kajian Multidisiplin | 405
menyelesaikan tugas yang diberikan guru, 3) membantu teman untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, 4) mencontek pada saat ujian/tes, 5) membuat catatan kecil untuk dicontek pada saat ujian/tes, 6) memberikan contekan teman pada saat ujian/tes, 7) Saling tukar jawaban kepada teman. Mencontek adalah masalah yang besar bagi sistem pendidikan suatu bangsa, di Tunisia ditemukan paling tidak ada 70% siswa mencontek dan pernah melakukan minimal sekali dalam masa studi [15]. Nilai-nilai karakter yang diimplementasikan untuk mencegah terjadinya kecurangan akademik di Era Pandemi
Pengenalan lingkungan sekolah yang setiap tahun dilaksanakan pada saat era pandemik menjadi hambatan, namun demikian nilai-nilai pendidikan karakter tetap harus ditanamkan mulai dari melatih kedisiplinan siswa, ketertiban, kejujuran, tanggungjawab, serta pembinaan mental harus tetap dilakukan melalui pembelajaran daring yang dikemas dalam penyusunan kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat nilai-nilai kejujuran yang terukur melalui proses pembelajaran daring. Hal ini perlu ditekankan karena, di era covid-19 dengan model pembelajaran daring ini rentan meningkatnya tingkat kecurangan akademik yang relatif tinggi. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang perlu segera diatasi sekolah, karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap karakter siswa terutama terkait dengan perkembangan pribadi siswa yang harus dikontrol ketika berhadapan dengan teknologi yang bebas dan tidak didampingi guru secara langsung. Memang Ketika belajar di rumah siswa seharusnya didampingi oleh keluarga, akan tetapi berbagai kesibukan untuk mencari nafkah dan bertumpuknya tugas siswa telah menciptakan kebosanan yang dialami siswa dan keluarga. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, guru dituntut untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan kreatif dan inovatif dan dapat menambah motivasi, energi baru bagi siswa dan selalu menanamkan nilai-nilai karakter akhlakul karimah kepada siswa agar tidak melakukan kegiatan kecurangan akademik, baik di dalam maupun diluar kelas.
Pada pembelajaran daring seperti saat ini, maka pembiasaan untuk disiplin dalam proses pembelajaran seperti menampilkan performance yang baik saat melakukan zoom meeting/aplikasi google dengan guru, tidak arogansi, menyapa/mengucap salam dengan baik, bertutur kata dengan sopan pada saat berinteraksi dengan teman/guru, menumbuhkan semangat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, dan
406 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menggunakan teknologi dengan bijak. Pendidik menyelipkan nilai religious, nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, cinta damai, dan toleransi pada pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Akhirnya, pendidik harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini dengan kreatif, sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik [16] . Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajar-an daring ataupun saat pengumpulan tugas.
Pencegahan terjadinya kecurangan akademik juga dilakukan oleh guru pada saat siswa akan mengerjakan ulangan atau ujian dengan cara menasehati agar dalam mengerjakannya siswa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan kecurangan akademik, selain itu guru juga memberikan informasi terkait dengan reward yang akan didapat siswa jika siswa tidak melakukan kecurangan akademik dan akan memberikan punishment jika siswa melakukan kecurangan akademik. Reward bisa berupa: 1) memberikan pujian untuk kejujuran dan usaha kerasnya dalam mengerjakan tugas, 2) memberikan semangat untuk tetap bersikap jujur dan bertanggung jawab, 3) memberikan nilai tambah di mapel yang saya ajarkan dari aspek perilaku, sedangkan punishment guru biasanya melakukan tindakan: 1) menyobek LJK ketika ujian dan menggantikan dengan LJK yang baru, 2) membuat catatan khusus untuk proses penilaian di raport, 3) mengulang ujian atau tes yang sudah di lakukan, 4) mengerjakan ujian di depan guru.
Untuk mengatasi permasalahan pencegahan terjadinya kecurangan akademik yang sudah dilakukan oleh guru, ternyata belum dapat memberikan perubahan yang berarti bagi siswa, karena masih ditemukan banyak siswa yang masih tetap melakukan kegiatan kecurangan akademik meskipun sudah menerima sanksi yang telah diberikan oleh guru, hal ini dimungkinkan karena ada beberapa guru yang kurang konsisten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kecurangan akademik dengan membiarkan siswa mencontek pada saat ujian. Sekolah hanya bisa memberikan aturan lewat tata tertib selanjutnya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 407
diserahkan langsung penanganannya pada wali kelas maupun guru mata pelajaran terkait kecurangan siswa dan belum ada diskusi yang membahas permasalahan tentang pelanggaran siswa lebih jauh, selain itu adanya kebijakan sekolah yang tetap menaikkan siswa yang sering melakukan pelanggaran. Unttuk itu perlu diformulasikan untuk mencegah kecurangan akademik adalah dengan adalah dengan mengubah perilaku dan persepsi [7].
Pembelajaran Digital dan Life Skills
Pembelajaran digital merupakan tren pendidikan masa kini karena perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi pada era Industrial Revolution 4.0. yang meningkat tajam. Hal ini memiliki potensi dapat digunakan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan anak didik bukan saja dalam hal pengetahuan tetapi juga dalam life skills, khususnya dalam hal kreativitas inovatif yang menjadi modal penting dalam kehidupan era Abad 21 ini [16]. Dengan memanfaatkan media sosial secara umum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif, akan tetapi harus menggunakan media sosial tersebut secara efektif dengan cara mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pembelajaran kolaboratif melalui media sosial, dan niat untuk menggunakan media sosial secara positif berhubungan dengan interaktivitas siswa dengan teman sebaya, guru, atau pihak lain untuk meningkatkan prestasi belajar [17]. Siswa memiliki pendekatan dan gaya belajar yang berbeda-beda (partisipatif, kolaboratif, dan mandiri) dalam penggunaan teknologi media sosial, sehingga akan berpengaruh terhadap niat siswa dalam pembelajaran dan pembelajaran yang efektif [18].
Whatsapp sebagai salah satu media sosial paling berpengaruh dan banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Pada era digital saat ini sudah menggunakan gawai dalam aktivitas keseharian mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Namun, sebagian besar pelajar tersebut menggunakan aplikasi media sosial, khususnya Whatsapp hanya untuk bermedia sosial saja, padahal di dalam aplikasi tersebut, terdapat manfaat yang bisa meningkatkan kemampuan literasi digital [19]. Penggunaan situs jejaring/jaringan sosial online melalui WhatsApp efektif dan tidak sangat tergantung dari opini siswa penggunaannya, jika menggunakan gambar yang tepat maka akan membuat efektif sebuah pembelajaran, akan tetapi jika terdapat postingan yang berlebihan justru akan menciptakan ke mubadziran, maka penggunaan WhatsApp dalam proses Pendidikan diarahkan sebaiknya alat penunjang teknologi [20], [21]. Akan tetapi beberapa sekolah pembelajaran dengan menggunakan
408 | New Normal, Kajian Multidisiplin
berbagai macam aplikasi seperti ruang guru, class room, zoom, google doc, google form, maupun melalui grup whatsapp, dapat berjalan baik dan efektif sesuai dengan kreatifitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa, dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan untuk nilai harian siswa [11] .
Penutup
Prestasi akademik merupakan hal yang sangat penting, siswa memahami bahwa kecurangan akademik merupakan perilaku yang tidak terpuji, tetapi mereka pada saat terdesak akan melakukan bahkan dianggap sebuah kelaziman. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akademik, meliputi: a) individu atau pribadi, kepribadian, c) teman sebaya, d) situasi, e) self efficacy, f) perkembangan moral, dan religi. Nilai-nilai karakter yang diimplementasikan guru dalam mencegah terjadinya kecurangan akademik, dengan cara menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggungjawab disetiap kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, selain itu guru juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi kecurangan akademik oleh siswa dengan melakukan pembelajaran daring berbasis pada nilai-nilai karakter baik pada saat interaksi dan komunikasi melalui daring maupun kedisiplinan sebagai siswa yang bertanggungjawab untuk mencapai ketuntasan belajar dengan diperolehnya kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi lebih berkualitas, sehingga tujuan untuk mewujudkan konsep pembelajaran abad 21 yang memuat niali-nilai Creativity and Innovation, Collaboration, Communication, Critical Thinking and Problem Solving dapat diwujudkan. Untuk itu perlu disusun Standart Operating Procedure (SOP) pembelajaran daring sebagai panduan penyelenggarannya, supaya dapat dihasilkan pembelajaran online yang optimal.
Rujukan
[1] F. R. Hariri, Ayub Wijayati Sapta Pradana, “Mendeteksi perilaku kecurangan akademik dengan perspektif,” vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2018.
[2] A. Info, “The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of ‘ Merdeka Belajar ,’” vol. 1, no. 1, pp. 38–49, 2020.
[3] O. I. Handarini and S. S. Wulandari, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home ( SFH ) Selama Pandemi Covid 19 Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home ( SFH ) …
New Normal, Kajian Multidisiplin | 409
..,” vol. 8, no. 1, pp. 496–503, 2020. [4] A. D. Tantama, I. Isharijadi, E. Era, and P. Korespondensi,
“Determinan perilaku kecurangan akademik dengan menggunakan fraud diamond dan perspektif diri mahasiswa pendidikan akuntansi,” vol. 22, no. 2, pp. 185–196, 2020.
[5] F. Aulia, P. S. Psikologi, F. I. Pendidikan, and U. N. Padang, “Faktor-faktor yang terkait dengan kecurangan akademik pada mahasiswa,” pp. 23–32.
[6] S. E. Küçüktepe, “Evaluation of tendency towards academic dishonesty levels of psychological counseling and guidance undergraduate students,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 15, pp. 2722–2727, 2011.
[7] D. Purnamasari, “faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik pada mahasiswa Desi,” Educ. Psychol. J., vol. 2, no. 1, pp. 65–72, 2013.
[8] A. Kushartanti, “Perilaku Menyontek ditinjau dari Kepercayaan Diri,” Indig. J. Imliah Berk. Psikol., vol. 11, no. 2, pp. 38–46, 2009.
[9] I. Murdiansyah, M. Sudarman, and Nurkholis, “Pengaruh Dimensi Fraud Diamond Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik,” J. Akunt. Aktual, vol. 4, no. 2, pp. 121–133, 2017.
[10] H. Wijaya, S. Tinggi, and F. Jaffray, “Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbasis Media Sosial,” no. August, 2019.
[11] W. Aji, F. Dewi, U. Kristen, and S. Wacana, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di,” vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2020.
[12] L. A. Khoiroh, Ni’matul, Munoto, “Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning dan Motivasi belajar terhadap Hasil belajar Siswa,” 2018.
[13] C. Girvan, C. Conneely, and B. Tangney, “Extending experiential learning in teacher professional development,” Teach. Teach. Educ., vol. 58, pp. 129–139, 2016.
[14] M. Nurtanto, M. Fawaid, and H. Sofyan, “Problem Based Learning (PBL) in Industry 4.0: Improving Learning Quality through Character-Based Literacy Learning and Life Career Skill (LL-LCS),” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1573, p. 012006, 2020.
[15] J. Hamani, “The Exam Cheating among Tunisian Students of the Higher Institute of Sport and Physical Education of Sfax,” IOSR J. Humanit. Soc. Sci., vol. 15, no. 6, pp. 90–95, 2013.
410 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[16] U. Khasanah and Herina, “Prosiding seminar nasional pendidikan
program pascasarjana universitas PGRI palembang,” Membangun Karakter Siswa Melalui Literasi Digit. Dalam Menghadapi Pendidik. Abad 21 (Revolusi Ind. 4.0), vol. 2, pp. 999–1015, 2019.
[17] W. M. Al-Rahmi, M. S. Othman, and L. M. Yusuf, “The role of social media for collaborative learning to improve academic performance of students and researchers in Malaysian higher education,” Int. Rev. Res. Open Distance Learn., vol. 16, no. 4, pp. 177–204, 2015.
[18] V. Balakrishnan and C. L. Gan, “Students’ learning styles and their effects on the use of social media technology for learning,” Telemat. Informatics, vol. 33, no. 3, pp. 808–821, 2016.
[19] M. W. Sahidillah and P. Miftahurrisqi, “Whatsapp sebagai Media Literasi Digital Siswa,” J. VARIDIKA, vol. 1, no. 1, pp. 52–57, 2019.
[20] L. Cetinkaya, “International Review of Research in Open and Distributed Learning The Impact of Whatsapp Use on Success in Education Process,” Int. Rev. Res. Open Distrib. Learn., vol. 18, no. 7, pp. 1–8, 2018.
[21] G. Veletsianos and C. C. Navarrete, “1078-Article Text-9250-2-10-20120709.”
New Normal, Kajian Multidisiplin | 411
Bab 26
Pembelajaran Bahasa Indonesia Berorientasi Kecakapan Hidup bagi Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19 Daroe Iswatiningsih30
Pengantar
Kondisi saat ini masih ditengarai sebagai suatu keadaan yang terdampak akibat virus Corona 19 yang dikenal dengan pandemi Covid 19. Keadaan ini sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan, mulai dari kesehatan pada khususnya, ekonomi, sosial, pendidikan, seni dan budaya serta bidang lain [1]-[3]. Terkait dengan dampak Covid 19 pada bidang pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19)[4]. Ada enam aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam surat edaran tersebut, satu di antaranya adalah proses belajar dari rumah (BDR). Belajar dari rumah merupakan upaya mengantisipasi penyebaran virus serta ternjangkitnya peserta didik yang memang rentan terhadap kondisi ini.
Penyelenggaraan pembelajaran dalam masa Covid 19 ini, pemerintah memberikan dispensasi atau pengecualian dalam hal proses, capaian, dan evaluasi yang lebih sederhana dari sisi guru dan peserta didik serta lebih bermanfaat bagi siswa. Ada empat hal yang menjadi penekanan selama belajar di rumah, yakni (1) bahwa selama belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, diharapkan pembelajaran memberikan pengalaman bermakna bagi siswa, (2) pembelajaran hendaknya difokuskan pendidikan kecakapan hidup di antaranya mengenai pandemi Covid 19, (3) penugasan yang diberikan kepada siswa dapat bervariasi antarsiswa dengan menyesiaikan minat dan kondisi siswa, dan (4) produk penugasan yang diberikan guru pada siswa selama belajar dari rumah dapat berupa umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna.
Jika dicermati secara seksama empat aspek yang tertuang dalam surat edaran Kemendikbud di atas, bahwa selama pembelajaran yang
30 Dr. Daroe Iswatiningsih Dosen Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah
Malang
412 | New Normal, Kajian Multidisiplin
berlangsung dari rumah melalui daring atau yang bersifat jarak jauh ini memberikan keleluasaan bagi guru dalam berinisiatif merancang konten dan penugasan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup peserta didik dan mampu mengevaluasi penuh manfaat. Untuk itu yang perlu dipikirkan guru adalah bagaimana menyusun dan mengembang-kan materi dan penugasan yang menggali, menumbuhkan dan meningkatkan kecakapan hidup peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Terlebih lagi mengingat situasi dan kondisi berlangsungnya pembelajaran jarak jauh ii akbiat pandemi Covid 19.
Dalam masa pandemi ini, pemerintah benar-benar memperhati-kan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan hingga menerbitkan kembali Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19. Ada empat tujuan dengan dikeluarkannya surat edaran ini, yakni (1) sebagai pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Covid 19, (2) melindungi warga sauan pendidikan dari dampak buruk covid 19, (3) mencegah penyebaran dan penlaran covid 19 di satuan pendidikan, dan (4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial pada peserta didik, dan orang tua atau wali [5]. Penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi pada tahun ajaran baru 2020/2021 mendapat perhatian dari empat menteri, yakni Menteri Pendidian dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan bahwa peserta didik yang berada di Zona hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Namun, dalam perkembangan zona hijau dan kuning diperboleh-kan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini benar-benar mendapat perhatian yang serius.
Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang saling berjauhan antara guru dan peserta didik dengan memanfaatkan perangkat teknologi, seperti hanphone, laptop, komputer atau jaringan internet lain. Selain aspek jarak, tempat juga aspek waktu yang menentukan berlangsungnya pembelajaran jarak jauh. Dalam kajian ini, penulis hanya mengemukakan apa yang harus dipersiapkan guru bahasa Indonesia dalam membelajarkan materi guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta didik yang berorientasi pada kecakapan hidup. Kecapakapan hidup apa saja yang diajarkan guru agar dapat dikembangkan oleh peserta didik sebagai capaian pembelajaran bahasa
New Normal, Kajian Multidisiplin | 413
Indonesia. Tulisan ini berangkat dari hasil pengamatan, survei di lingkungan, dan kajian pustaka selama masa pandemi Covid 19 dalam pembelajaran. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yakni: Persiapan apa sajakah yang dilakukan guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran daring di masa pandemi? Kecakapan hidup apa sajakah yang diajarkan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia?
Pembahasan
Persiapan Guru dalam Pembelajaran di Masa Pandemi
Tidak diprediksikan bahwa tersebarnya wabah virus Corona sangat berpengruh terhadap situasi dan kondisi pembelajaran di Indonesia. Sejak diumukannya proses belajar yang dilakukan dari rumah pada 16 Maret 2020 oleh pemerintah, membuat guru kelabakan, sebab tanpa persiapan yang memadai untuk meerapkannya. Dari proses pembelajaran secara fisik, klasikal di kelas serta lebih banyak bersifat ceramah, tiba-tiba guru harus melakukan secara online, jarak jauh dan memanfaatkan teknologi (HP, laptop, komputer, serta berbagai aplikasi), serta dukungan internet (kuota dan jaringan yang memadai). Tentu hal ini menuntut guru melakukan persiapan yang baik.
Beberapa persiapan yang dilakukan guru guna memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi Corona virus diseases (Covid 19) ini mulai dari yang sederhana hingga komplek. Secara umum, persiapan yang dilaukan guru yakni, (1) beradaptasi menggunakan peragkat belajar online/daring seperi whatsapp, email, web sekolah, Youtube, google classroom, google meeting, Rumah Belajar Kemendikbud, dan yang lain, (2) menyiapkan bahan pembelajaran, (3) menyiapkan tugas dan aktivitas kegiatan siswa, dan (4) menyiapkan evaluasinya. Persiapan guru yang terekam penulis meliputi: a) menyiapkan materi, b) menyiapkan media pembelajaran (video, ppt, foto), c) membuat kuis, dan d) membuat peugasan. Selain persiapan pembelajaran, guru juga membangun komunikasi dan interaksi dengan orang tua siswa dalam mendukung kelancaran aktivitas belajar anak selama belajar dari rumah (BDR). Interaksi guru dengan orang tua siswa ini juga tidak selamanya mudah dan berjalan lancar, apalagi orang tua yang tingkat pemahaman pendidikan yang masih kurang, orang tua yang tidak memiliki waktu penuh mendampingi anak, dan orang tua yang tidak sabar membantu anak belajar.
Peran sekolah sangat penting saat mengawali pembelajaran yang bersifat online atau daring. Kepala sekolah memberikan penguatan,
414 | New Normal, Kajian Multidisiplin
arahan dan monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru; menyampaikan surat pemberitahuan kepada siswa dan orang tua pelaksanaan pembelajaran daring, alasan dan menjaga kewaspadaan anak selama belajar di rumah [6].
Persiapan mengajar guru pada awalnya lebih menyesuaikan dengan program semester (promes) yang telah dibuat. Materi yang diajarkan memindahkan yang sifatnya dari kelas ke rumah. Siswa dan orang tua merasa tersita waktu dengan materi yang dibaca dari buku paket serta tugas yag harus dikerjakan. Waktu pelaporan tugas pun telah ditentukan guru sesuai jadwal yang diberikan dan ditetapkan guru. Namun dalam perkembangannya, pelaporan tugas sisa lebih fleksibel dikarenakan berbagai kendala, seperti jaringan beban kuota, jaringan internet yang kurang bagus, serta kesibukan orang tua yang bekerja.
Persiapan guru setelah pembelajaran berjalan dua bulan lebih tertata, khususnya dalam mengelola tugas dan aktivitas siswa. Aktivitas pelaporan tugas siswa, khususnya yang di sekolah dasar sudah disesuaikan dengan keadaan keluarga/orang tua peserta didik. Hal ini juga sebagaimana Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran di masa darurat Covid 19. Siswa jangan terlalu dibebani tugas, capaian pembelajaran jangan dilaksanakan sesuai kurikulum, kegiatan belajaran bervariatif sesui dengan minat dan karakteristik peserta didik, ditekankan pada kebermaknaan dan keca-kapan atau keterampilan hidup, seperti pandemi covid 19 dan penilaian dapat dilakukan secara kualitatif (tidak harus skor).
Karena banyaknya kendala di lapangan/masyarakat terhadap pelaksanaan pembelajaran daring, maka aplikasi yang mudah digunakan siswa dan orang tua, seperti WhatsApp, yakni bagi siswa kelas 1 – 3 Sekolah Dasar dan kelas 4 – 6 menggunakan Google Classroom [7]. Beberapa sekolah telah melakukan pembelajaran online, misalnya menggunakan Google Aplication for Education (GAFE) dengan classroom. Tentu hal ini akan memudahkan guru dan siswa baik dalam mengunngah tugas, ulangan, dan ujian. Ketidakmerataan fasilitas sekolah, ekonomi keluarga, dan daya paham orang tua menjadi kendala dalam pembelajaran bersifat online.
Kecakapan Hidup dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia
a) Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia
Sebelum mengulas tentang pembelajaran, tentu dipahami dahulu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam bernegara. Terdapat dua
New Normal, Kajian Multidisiplin | 415
kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni sebagai (1) bahasa nasional dan (2) sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional memili empat fungsi, yakni (a) lambang kebanggan nasional, (b) lambang identitas nasional, (c) alat pemersatu bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasa, dan (d) alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara memiliki empat fungsi, yakni (a) sebagai bahasa remi kenegaraan, (b) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (c) alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (d) alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern [8].
Dengan kedudukan dan fungsi yang besar ini, bahasa Indonesia memiliki peran strategis yang bersifat internal dan eksternal. Maksudnya, fungsi bahasa secara internal adalah mengokohkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui bahasa sebagai pemersatu bangsa akan menguatkan fungsi kenegaraan sebagai jati diri bangsa. Adapun peran bahasa secara eksternal adalah dengan menunjukkan keberadaan dan identitas bangsa Indonesia di kancah dunia atau internasional. Bahasa Indonesia sebagai indentitas dan kebanggaan bangsa akan ditunjukkan pada dunia. Untuk itu, agar tujuan dari fungsi tersebut dapat ditunjukkan sebagai pemersatu dan lambang identitas bangsa, maka pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berbahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh semua warga negara Indonesia.
Bertolak dari paparan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, maka hakikat pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya adalah membeajarkan peserta didik agar terampil atau memiliki kecakapan hidup yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis [9],[20]. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Indonesia peserta didik memiliki sikap menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara serta meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional dan sosial. Adapun pada pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,
416 | New Normal, Kajian Multidisiplin
budi pekerti, meningkatkan pengetahuan, menghargai, dan membangg-akan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
Dengan demikian, belajar bahasa dan sastra Indonesia dapat menumbuhkan dan membangun kecintaan, komitmen serta integritas peserta didik atas Kehidupan berbangsa dan bernegara secara keselu-ruhan. Peserta didik menjadi individu-individu yang berkompeten dari aspek pengetahuan, sikap, dan skill. Karakter-karakter yang ditumbuh-kan pada peserta didik ini merupakan implementasi dari lima nilai utama karakter, yakni nasionalis, religius, gotong royong, mandiri, dan integritas.
b) Prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia
Belajar bahasa adalah belajar agar mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan konteks yang yang ada. Berkomunikasi dapat dinyatakan lisan atau tulisan. Untuk untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sarana bahasa dibutuhkan pemahaman topik yang dikomunikasikan, lawan bicara, tempat dan tujuan. Dalam kenyataan-nya, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas lebih ditujukan pada aspek pengetahuan tentang teori kebahasaan, mulai dari pengetahuan ejaan dan tata tulisnya (aspek kebahasaan), ciri-ciri teks, prinsip menulis, dan sebagainya. Hal ini menjadikan kesempatan untuk praktik berbahasa diabaikan. Untuk itu, beberapa pandangan tentag prinsip pembelajaran bahasa Indonesia juga berorientasi atau menunjang pada kecakapan hidup (life skill)
Ada empat keterampilan yang dikuatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini secara terpadu berlangsung dalam pembelajaran, baik yang digerakkan oleh guru maupun siswa. Proses pembelajaran akan berlangsung secara dinamis apabila bentuk komunikasi berlangsung melalui keempat keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis untuk menghindarkan kejenuhan [10]. Guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan metode dan stategi pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik. Namun demikian, menurutnya, guru tetap mengupayakan metode dan teknik dalam menyampaikan materi agar tidak jenuh dan membosankan. Selain itu, prinsip yang perlu dipahami guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia, yakni pengintegrasian antara bentuk dan makna serta penekanan pada kemampuan berbahasa praktis, seperti interaksi antara
New Normal, Kajian Multidisiplin | 417
guru dan siswa sehari-hari penuh kesopanan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi berguna atau bermakna (meaningfull) bagi siswa.
Pandangan di atas sebagaimana arah pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013, lebih berbasis pada teks [11]. Dalam hal ini, teks yang dibangun bertujuan agar dapat membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Dalam penerapannya, pembelajaran Bahasa Indonesia diorientasikan pada empat prinsip, yaitu (a) bahasa hendak-nya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan, (b) penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasan untuk mengungkapkan makna, (c) bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks, karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakai/penggunanya, dan (d) bahasa merupakan sarana pembentuk-an berpikir manusia.
Dengan prinsip di atas, maka pembelajaran bahasa berbasis teks membawa implikasi metodologis pada pembelajaran yang bertahap [12]. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks mampu membawa peserta didik beraktivitas secara kreatif. Hal ini diawali dari kegiatan guru membangun konteks, dilanjutkan dengan kegiatan pemodelan, mem-bangun teks secara bersama-sama, sampai pada membangun teks secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan karena teks merupakan satuan bahasa yang mengandung pikiran dengan struktur yang lengkap. Meskipun sudah dibuat pedoman dalam membelajarkan bahasa Indonesia yang lebih bermakna bagi peserta didik namun masih banyak guru yang terjebak pada pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan pada peserta didik bertujuan untuk melatih peserta didik terampil berbahasa dengan menuangkan ide dan gagasanya secara kreatif dan kritis, namun kenyataannya banyak guru terjebak dalam tataran konsep sehingga pembelajaran cenderung membahas teori-teori Bahasa [13]. Hal ini sering menjebak dan membinggungkan siswa saat mengikuti ujian. Teori-teori bahasa diharapkan hanya sebagai pendukung atau penjelas dalam konteks, yaitu yang berkaitan dengan keterampilan tertentu yang diajarkan. Misalnya saat menulis laporan hasil observasi, dan ditemukan banyak kesalahan penulisan maupun ejaan, maka guru sekaligus memberi penguatan perbaikan kesalahan peserta didik.
418 | New Normal, Kajian Multidisiplin
c) Keterampilan Berbahasa sebagai Kecakapan Hidup
Pendidikan saat ini menekankan penguasaan kemampuan atau keterampilan tertentu yang dikuasai para lulusan agar mandiri dan survive di lingkungannya. Kondisi ini tidak terlepas dari fakta tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK setiap tahunnya [14]. Sumber daya manusia Indonesia yang potensial ini apabila tidak dimanfaatkan dan didayagunakan dengan baik dan efisien akan menimbulkan persoalan pertumbuhan ekonomi terlebih lagi Indonesia akan mendapat bonus demografi pada rentang waktu 2030-2040. Penduduk dengan usia produkrif (15-64 tahun) sebayak 64 persen dari jumlah penduduk ini diprediksikan akan memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi apabila dapat dikelola dengan baik, khususnya apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan [15].
Ada sepuluh kecakapan hidup yang penting dimiliki oleh individu, yakni kecakapan memecahkan masalah (problem solving skills), berpikir kritis (critical thinking), membuat keputusan (decision making), membangun hubungan antarpribadi (interpersonal relation), kepedulian (empathy), mengenali diri sendiri (self awarness buliding), berkomunikasi secra efektif (effective communication skill), berpikir kreatif (creative thinking), kemampuan mengatasi emosi (coping with emotion) dan kemampuan mengatasi stress (coping with strss skill[16]. Kesiapan sesorang melengkapi dirinya dengan kecakapan hidup ini akan membuatnya dapat bersaing di dunia kerja terlebih lagi menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Dunia pendidikan perlu merespon dalam mengimplementasikan dalam berbagai program pembelajaran. Keca-kapan hidup (life skills) merupakan potensi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan sebagai bekal hidup di masyarakat. Kecakapan yang dimiliki seseorang ini dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Seseorang yang memiliki kecakapan hidup akan lebih memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan bersosialisasi di masyarakat. Pendidikan di Indonesia telah dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter dan berilmu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3. Selanjutnya pendidikan harus mampu merealisasikan tujuan dan cita-cita mencerdaskan warga bangsa ini sesuai dengan harapan, yakni menjadi lulusan yang mandiri dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 419
produktif, bertanggung jawab akan peran dan tugas, mampu memecah-kan masalah, inisiatif, dan kreatif.
Kecakapan hidup merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk mau dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Seseorang yang memiliki keckapan hidup diduung sikap kreatif dan bernalar [17]. Pada masa seperti sekarang ini, yakni masa pandemi membuat banyak orang tertekan, cemas, dan menderita akibat diberhentikan dari perusahaan, usaha berhenti, pendapatan tidak maksimal, tidak dapat berinteraksi, belajar tidak maksimal, tuntutan penguasaan teknologi semakin tinggi, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki kecakapan hidup, minimal akan berusaha beradaptasi dengan kondisi dan segera mencari solusi untuk keberlangsungan hidup.
Kemampuan seseorang untuk mudah beradaptasi pada lingkungan merupakan sikap berkarakter, yakni mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah tentu berangkat dari pemahaman dari aspek kognitif dan usaha belajar yang sungguh-sungguh. Terdapat tiga langkah dalam memecahkan masalah, yakni membaca situasi, menyusun strategi dan eksekusi [18). Langkah pertama membaca situasi, dapat diartikan mengenali situasi. Dengan mengenali situasi yang ada serta persoalan yang terjadi, selanjutnya seseorag aka menyusun strategi dalam memecahkan masalah yang ada. Strategi yag telah direncanakan dan disusun selajutnya perlu dieksekusi, yakni ditidaklanjuti untuk merealisasikannya. Sikap seseorang yang demikian, dapat dikatakan sikap bernalar kritis. Implementasi dari penguatan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi bernalar kritis, mandiri, kreatif, sikap gotong royong, sikap kebhinekaan global, dan berakhlak mulia [19]. Keenam sikap tersebut oleh Nadiem ditetapkan sebagai profil pelajar Indonesia Pancasila. Pelajar Indonesia yang memiliki keenam profil ini tentu mampu bersaing dalam kehidupan di masyarakat. Berikut contoh kompetensi dasar (KD) dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diturunkan ke dalam indikator ketercapaian kompetensi dan bwntuk kecakapan hidup yang ditumbuhkan selama pembelajaran.
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan mampu mengembangkan empat keterampilan berbahasa, yakni (a) menyimak, (b) berbicara, (c) membaca, dan (d) menulis. Keempat keerampilan ini saling menyatu dalam sebuag penguasaan berbahasa. Demikian halnya dalam pembelajaran sastra,
420 | New Normal, Kajian Multidisiplin
maka keempat keterampilan tersebut secara implisit terintegrasi di dalamnya. Sastra merupakan wahana dalam mewadahi konsep, pikiran serta ekspresi peserta didik dengan menggunakan bahasa yang indah. Tentu saja, peserta didik untuk mampu menghasilkan sebuah karya sastra yang indah, menarik dan memiliki kekuatan imajinatif diperlukan keterampilan membaca, keterampilan berolah rasa dalam bahasa tulis, dan keterampilan mengomunikasikan karya yang diciptakannya.
Tabel 1. Contoh KD, Indikator dan Kecakapan Hidup Kompetensi Dasar Indikator capaian
pembelajaran Kecakapan Hidup
3.11 Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya (film, cerita, puisi, novel, karya seni) yang dibaca atau diperdengar-kan
Menyebutkan kualitas peran masing-masing tokoh dalam film pendek yang disajikan
Menyebutkan unsur-unsur menarik dari puisi yang dibaca
Berpikir krtis (Critical thinking)
4.11 Menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya (film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah) yang dibaca atau didengar
Bercerita kualitas peran tokoh, setting tempat, alur cerita dalam film pendek yang ditonton
Membacakan kualitas puisi yang dibaca (amanat, rima, gaya bahasa)
Pengambilan keputusan (Decision making) Berkomunikasi secara efektif (Effective commuication)
3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar
Menyebutkan contoh ungkapan yang menyatakan simpati, peduli, empati
Mengenali ungkapan yanga menyatakan simpati, peduli, empati
Sikap empati (empathy) Kesadaran diri (awareness)
4.11 Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar
Membuat cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati atau rasa peduli
Membacakan cerita yang berisi ungkapam simpati atau rasa peduli
Berpikir kreatif (Creatif thinking) Kemampuan membangun hubungan diri dengan orang secara baik (Interpersonal relationship)
New Normal, Kajian Multidisiplin | 421
Tabel 2. Kegiatan Pembelajaran yang Mendukung Kecakapan Hidup Siswa
Ketrampilan Berbahasa
Kegiatan pembelajaran
Kecakapan Hidup di Masyarakat
Manfaat
Menyimak Menyimak pesan Mengambil inti pesan Siswa mampu menyimak berbagai hal dengan baik
Menyimak berita Menemukan pesan berita
Menyimak penjelasan
Memahami hal yang dijelaskan
Berbicara Bertelepon Mampu bertelepon dengan baik
Siswa mampu melakukan berbagai aktivitas berbicara sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaan denga sopan, jelas, tepat, efektif, menarik dan mengesankan
Bernegosiasi Mampu melakuan negosiasi (penawaran, penjualan, meyakinkan)
Menyampaikan pesan/maksud
Mampu menyampaikan pesan / maksud dengan baik, jelas dan efektif
Menyampaikan berita
Mampu menyampaikan berita secara dan aktual
Berwawancara Mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan dengan baik
Bercerita /Story telling
Mampu berceita dengan runtut dan menarik
Berdebat Mampu berdebat sesuai dengan ketentuan (dengan baik)
Berpidato Mampu mengungkapkan pikiran dan maksud dalam sebuah forum/ kegiatan
Membaca Membaca pesan/surat
Memahami isi surat secara lengkap
Siswa mampu membaca berbagai teks, buku dengan fokus, cermat dan mampu menemukan pesan, maksud dan isi bacaan
Membaca pengumuman
Memahami isi pengumuman
Membaca berita Memahami dan menemukan pesan berita
Membaca buku/cerita
Memhami dan menemukan isi/pesan buku /cerita
Menulis Menulis surat Mampu menulis surat dengan baik
Siswa dapat melakukan berbagai aktivitas menulis sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaan dengan baik, jelas, efektif, tepat memenuhi kaidah kebahasaan
Menulis pesan Mampu menulis pesan secara singkat dan jelas
Menulis pengumuman
Mampu menulis pengumuman
Menulis catatan Mampu menulis catatan secara jelas dan runtut
Menulis laporan Mampu menulis hal-hal yang dilaporkan
Menulis berita Mampu menulis hal yang ingin diberitakan
Menulis cerita Mmampu menulis cerita yang menarik dan mendidik
422 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Demikian halnya dengan keterampilan menyimak dan berbicara.
Seorang pendengar yang baik, fokus dan kritis akan mampu menyerap informasi dengan baik dan menuangkannya dalam bentuk komunikasi lisan atau tulisan. Kemampuan menyimak ini juga penting dimiliki oleh peserta didik agar mendapatkan data atau informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Peserta didik tidak mudah menerima informasi yang tidak jelas sumber dan isinya. Tentu hal ini sekarang banyak terjadi di era teknologi informasi berkembang dengan pesat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chamot dan Kupper menunjukkan bahwa siswa-siswa yang sukses adalah mereka yang menfokuskan secara selektif pada konteks dari teks selama fase menyimak [20]. Pemahaman dari hasil menyimak dapat ditunjukkan dari pengolahan data yang tepat. Dalam era teknologi saat ini, menyimak dan membaca merupakan aktivitas yang penting dikuasai karena banyaknya informasi yang didapat, meskipun tanpa dicari. Karakter jujur, terpercaya, dan bertanggung jawab pun perlu dikuatkan pada peserta didik agar dapat menggunakan informasi sebaik mungkin dan tidak bertentangan dengan hukum.
Kecakapan hidup yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia banyak sekali dan dapat dicpai dengan menggunaan berbagai metode dan strategi. Terdapat delapan metode pembelajaran yang membangun kecakapan hidup peserta didik, yakni diskusi kelas classroom discussions), tugas kelompok (group tasks), permainan yang mendidik (education games), bermain peran (role plays), debat (debates), curah pendapat (brainstorming), studi kasus dan analisis case studies and analysis), dan bercerita (story telling) [21]. Selama proses pembelajaran, guru dapat menerapkan metode-metode tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dikuasai peserta didik, misalnya siswa dapat menceritakan tokoh yang dikagumi, maka metode bercerita akan sesuai untuk menyapaikan tokoh yang mengispirasi atau dikagumi tersebut. Dengan kemampuan bercerita secara runtut dan mengesankan, maka kecakapan hidup sosial (social skills) akan terbangun pada diri peserta didik.
Berbagai keckapan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga katergori, kecakapan hidup kognitive skills, social skills, dan negotiating skill atau coping skills). Kecakapan hidup dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang bertolak dari empat keterampilan berbahasa beserta kegiatan pembelajaran serta manfaatnya sebagaimana ditapilkan dalam tabel 2.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 423
Penutup
Pembelajaran bahasa Indonesia diberikan pada peserta didik mulai dari tigkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam kurun waktu yang relatif lama untuk belajar bahasa Indonesia, tentu banyak pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Demikian halnya belajar bahasa Indonesia guna menumbuhkan sikap dan kakarter peserta didik. Bahasa merupaka cerminan budaya masyarakat pemilik bahasa. Oleh karena itu, belajar bahasa Indonesia sekaligus mempelajari budaya yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan hidup ini tentu juga membangun sikap dan karakter peserta didik agar mampu hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, baik dari aspek bahasa, sosial, budaya, serta yang lain. Dengan kecakapan hidup yang bersumber dari bahasa, maka keberagaman yang ada di masyarakat merupkan potensi besar dalam berkreasi dan berinovasi.
Rujukan
[1] Aji, Rizqon halal Syah. “Dampak Coovid 19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah Keterampilan dan Proses pembelajaran”. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7, No. 5, 2020.
[2] Pitaloka, Herninda et all. “The Economic mpact of the Covid 19 Outbreak: Evidance from Indonesia”. Jiko: Journal Ekonomi Indonesia, Vol.5, No.2, 2020.
[3] Zaharah Zaharah, Galia Ildusovna Kirilova, Anissa Windarti. “Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia.” Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7, No. 3, 2020.
[4] Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentag Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 2020.
[5] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa darurat Penyebar-an Corona Virus Disease (Covid-19). 2020.
[6] Kompas.com. “Panduan 5 Proses belajar di Rumah untuk Sekolah dan Orang Tua”. 17 Maret 2020. https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/17/121116571/panduan-5-tahap-proses-belajar-di-rumah-untuk-sekolah-dan-orangtua?page=all. Diakses tanggal 16 Agustus 2020.
424 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[7] BBC News Indonesia. 2020. “Virus Corona: Tak Semua Pengajar,
Siswa siap terapkan sekolah di rumah”. 18 Maret 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51906763. Diakses pada 15 Agustus 2020.
[8] Karyati, Tri. “Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam kehidupan Berbanngsa dan Bernegara”. Culture, Vol. 2, No. 1, Mei 2015.
[9] Atmazaki. “Mengungkap Masa Depan: Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Konteks Pengembangan Karakter Cerdas”. Jurnal Artikulasi, Vol.8, No. 2, 2009.
[10] Iskandarwassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.2013.
[11] Saragih, Amrin. “Pembelajaran Bahasa Berbasis Teks dalam Kurikulum 3013”. Jurnal Medan Makna, Vol. 4, No. 2, hlm. 197-214, Desember 2016.
[12] Rahman, Aida Fitri, Atmazai, dan Abdurahman. “Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 7 No. 3 September 2018; Seri A 9-16.
[13] Khair, Ummul. 2018. “Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra (Basastra) di SD dan MI”. Ar-Riayah: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.
[14] Khurniawan, Arie Wibowo, dkk. 2019. “Profil Lulusan SMK terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018/2019”.Vocational Education Policy, White Paper. ISSN: 2685-5739, Vol. 1 Nomor 9 Tahun 2019.
[15] Kementerian PPN-Bappenas. Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/ Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf
[16] WHO. Skill for Health, Skill-based health education including life skill: An imortant component of a childifriendly/Health-Promoting School, Meaning of Life Skills Skill. 1997.www.who.org
[17] Depdiknas. Buku Saku: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas. 2006.
[18] Cahyani, Hestin dan Setyawati, Ririn Wahyu. “Pentingnya Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah melalui PBL untuk
New Normal, Kajian Multidisiplin | 425
Mempersiapkan Generasi Unggul Menghadapi MEA”. Prisma, Prosiding Seminar nasional Matematika X, 2016, Halaman 151-160.
[19] Kompas.com dengan judul "Mendikbud Nadiem: Ini 6 Profil Pelajar Indonesia", https://www.kompas.com/edu/read/2020/05/07/ 130140471/ mendikbud-nadiem-ini-6-profil-pelajar-indonesia. 2020.
[20] Ghazali, Syukur. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa: Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif. Bandung: Refika Aditama. 2010.
[21] Kumar, Pradeep. “Morality and Life Skills: The Need and Importance of Life Skills Education”. Interational Journal of Advanced Education and Research. ISSN:2455-5746, Impact Factor:RJIF 5.34. Vol. 2;i\Issue 4; July 2017; page No. 144-148. www.alleducationjournal.com, 2017.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 427
Bab 27
Covid-19 dan Perilaku Berbudiutama Nurcholis Sunuyeko, Rochsun, Harun Ahmad 31
Pengantar
Seperti memunculkan paradoks ketika mencermati kata Covid-19 dan Perilaku Berbudiutama sebagaimana pokok judul di atas. Kata Covid-19, terbayang pada peristiwa mematikan yang melanda penduduk dunia sejak enam bulan terakhir, ketika sejumlah media dunia menginformasikan adanya wabah penyakit yang menyerang penduduk Kota Wuhan Provinsi Hubei China. Gambaran bagaimana hiruk pikuk keadaan Kota Wuhan China di tengah pandemi Corona, dipaparkan secara runtut oleh M. Irfan Ilmie seorang wartawan Kantor Berita Nasional Antara [1]. Gambaran sebagai kota mati dan mencekam ketika Wuhan dianggap sebagai episentrum virus corona, dengan memberlaku-kan penutupan total (lockdown) wilayah kota, berharap bahwa virus tidak menyebar ke kota lain Negara itu. Usaha maksimal dilakukan pemerintah setempat melalui penerapan peraturan-peraturan untuk antisipasi penyebaran dalam skala luas. Namun upaya manusia berhenti pada batas ikhtiar, kenyataannya virus yang diberi nama Covid-19 menyebar di beberapa kota di China, seperti Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou layaknya kota mati sepi ditinggal penghuninya pulang kampung [2], virus itu pun hampir menyebar ke seluruh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia.
Selain merupakan peristiwa fenomenal di Kota Wuhan China, wabah penyakit menular Covid-19 telah menjangkiti masyarakat penduduk dunia lainnya. Sampai pertengahan tahun 2020 dampak virus ini belum juga usai, bahkan tidak sedikit warga dunia meninggal karenanya. Di Hubei saja, lebih dari 100 ribu terjangkit dan puluhan ribu meninggal karena serangan Covid-19 [1]. Sementara di Italia, justru memunculkan statemen kontra poduktif dari Wali Kota Vertova, Orlando Gualdi, bahwa dampak Covid-19 lebih buruk dari Perang Dunia II [3]. Di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda normal, bahkan data terakhir dampak Covid-19 per 14 Juni 2020 tercatat 857 kasus baru, dan total positif mencapai 38277 orang dan peringkat 31 dunia [4]. Untuk antisipasi penyebaran lebih luas, sejak diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada awal bulan Maret 2020, beberapa kota telah menetapkan
31 Dr. Nur Kholis S, Dr. Rochsun, Dr. Harun Ahmad, Dosen IKIP Budi Utomo, Malang
428 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dan memberlakukan peraturan-peraturan. Seperti, pembatasan total (Lockdown), Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dan pemberlakuan peraturan dengan istilah baru melalui sebutan Pengetatan Sosial Secara Mandiri (PSSM) [5].
Pemberlakuan peraturan-peraturan di masa pandemi Covid-19, selain berdampak pada sektor kesehatan masyarakat, ketika banyak orang berjatuhan sakit dan berobat di sejumlah rumah sakit. Juga sektor-sektor lainnya, seperti, sektor sosial ekonomi, ketika terjadi hilangnya mata pencaharian karena banyak para pekerja dan karyawan yang dirumahkan [6]. Apalagi beberapa sumber mengatakan jika dampak Covid-19 sektor ekonomi jauh lebih berat [7]. Dampak Covid-19 pada sektor politik keamanan ketika terjadi peningkatan kriminalitas akibat banyaknya pengangguran, ketika terbatasnya ruang gerak atau mobilitas masa. Begitu juga pada sektor pendidikan, ketika proses belajar mengajar di sekolah ataupun di kampus kurang maksimal karena harus tinggal di rumah [8]. Gambaran mencekam dan menegangkan meliputi masyarakat dunia, ketika mendengar kata Covid-19, padahal jika diambil hikmah di balik pandemi virus yang katanya mematikan itu, justru memaksa untuk tidak sekedar memahami tapi juga harus mengimplentasikan dalam tatanan kehidupan yang sudah digariskan melalui budaya tertib, budaya patuh, budaya patut, budaya manfaat dan budaya-budaya manusiawi lainnya. Ajaran-ajaran itu begitu saja lewat dan terkadang tidak membekas sedikitpun dalam perilaku kehidupan sebagaimana cita-cita sang penyampai risalah, yang diutus sebagai penyempurna akhlak [9] [14]. Sementara hiruk pikuk dunia lebih asyik menari-nari dalam pelanggaran terhadap kodrat manusia sebagai makhluk yang fitrahnya menerima kebenaran, hanya saja tidak mengetahui [10] [11]. Munculnya peraturan-peraturan dalam masa pandemi Covid-19 itu, terlepas dari pro dan kontra tidak lain adalah mendidik untuk mengambil pelajaran dari nilai-nilai kebudiutamaan, untuk kembali kepada suatu perilaku berbudiutama.
Perilaku berbudiutama merupakan jati diri setiap insan, berbeda dengan kata Covid-19. Perilaku berbudiutama bukan sekedar kata, melainkan merupakan implementasi dari fitrah Illahiyah [10]. Perilaku berbudiutama sesungguhnya merupakan produk dari watak, karakter, moral dan akhlak sebagai kodrat manusia. Hanya saja terkadang dapat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan bangsa dimana mereka berdomisili. Ketika kodrat itu mondominasi dalam kehidupan sehari-hari, tentu lebih memunculkan perasaan-perasaan yang mengarah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 429
kepada suatu keadaan aman, damai dan sentosa, dalam nuansa harmonis, namun jika yang mendominasi sebaliknya maka berdampak sangat fatal akibat ulah manusia itu sendiri. Peristiwa pandemi corona yang menyerang masyarakat dunia, dipahami karena dominasi budaya dan lingkungan menyimpang dari kodrat insaniyah, yaitu menyimpang dari kodrat berbudiutama. Suatu kodrat berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai etika, moral insaniyah, bersosial dan bermasyarakat yang bermartabat, hidup berdampingan saling memahami, peduli, membantu, tolong menolong sesama melalui budaya kemanfatan, kepatuhan, kepatutan, kepedulian, dan nasionalisme (atau dalam konteks Indonesia dikenal dengan nilai ke-Indonesia-an). Menyadari bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Sang Khalik, selayaknya memunculkan penghambaan semata-mata kepada Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, bukan menghamba kepada makhluknya berupa nafsu angkara. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri (mikrokosmos) dan alam (makrokosmos), sehingga mampu memakmurkannya dalam keseimbangan [12].
Pendidikan menjadi sangat penting ketika mengalami situasi pandemi virus corona seperti ini, karena pada dasarnya manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi. Melalui potensi yang dimiliki, pendidikan berperan mengarahkan potensi yang dimiliki itu kepada kodrat yang telah menjadi fitrah sebagai insan yang bermoral, beretika, bermartabat, berkarakter. Karena sejatinya pendidikan tidak hanya mengembangkan keilmuan sebagaimana konsep Unesco learning to know, learning to do, tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan berbudi utama learning to be, dan learning to live together [13]. Begitu juga dalam skala nasional Indonesia, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi sebagaimana kodrat manusia. Melalui pengembangan potensi itu diharapkan menjadi insan yang beriman, bertaqwa, berakhlak, sehat, dan mandiri. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan perilaku berbudiutama. Perilaku berbudiutama diikhtiari melalui pendidikan kebudiutamaan.
Pendidikan kebudiutamaan secara akademik merupakan pendi-dikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan akhlak yang bertujuan mengembangkan potensi insan untuk memberi-kan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Secara psiko-logis mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling, dan moral behavior, intellectual force dan moral force [14]. Secara praktis, mencakup sistem
430 | New Normal, Kajian Multidisiplin
penanaman nilai-nilai kebaikan, meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik berhubungan dengan sang Maha Pencipta (Khalik), sesama manusia, lingkungan, maupun bangsanya (nasionalism). Pendidikan kebudiutama-an menjadi urgen karena terdapat kandungan dimensi karakter, moral dan akhlak. Selama dimensi kebudiutamaan belum menjadi kreteria dalam pendidikan, selama itu pula pendidikan mengalami kesulitan untuk melakukan kontribusi dalam pembangunan karakter. Karena dalam kenyataannya, pendidikan karakterlah yang menghasilkan sumber daya manusia handal dan memiliki jati diri. Akhlak atau moral yang yang dimiliki dan terejawantahkan dalam diri seseorang, sehingga ia menjadi insan yang berkarakter (good character), yaitu memiliki sikap jujur, sabar, rendah hati, tanggung jawab, dan rasa hormat, yang tercerminkan dalam kesatuan organisasi pribadi yang harmonis dan dinamis.
Uraian pada pengantar di atas dimaksudkan untuk mengantarkan pada pembabasan selanjutnya, yaitu bagaimana dua kata Covid-19 dan perilaku berbudiutama sebagaimana judul di dalam bookchapter dapat dijelaskan. Secara lebih jauh mungkin pembahasan kurang memenuhi harapan pembaca ketika menghubungkan keduanya. Namun, pembahasan di dalam tulisan ini merupakan keberanian tersendiri ketika mayoritas penduduk dunia sepakat jika Covid-19 adalah virus mematikan dan berdampak negatif pada sisi kehidupan umat manusia. Berbeda pada tulisan ini, ketika memandang Covid-19 sebagai penguat sarana pendidikan kebudiutamaan, untuk meraih perilaku berbudiutama. Para ahli sepakat bahwa menanggulangi Covid-19 meskipun belum ditemukan vaksinnya, tetapi ada cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kondisi kekebalan tubuh (imun). Menurut mereka untuk meningkatkan imun dapat dilakukan salah satunya dengan cara menghindari stress. Pada tulisan ini peristiwa Covid-19 menjadi pelajaran dan menjadi penguat pendidikan kebudiutamaan, di mana tujuan akhirnya adalah menghasilkan perilaku berbudiutama. Tokoh komedi terkenal pada jamannya Kelik Pelipur Lara dalam bukunya “Stop Stress”, memandang fenomena Covid-19 dalam suatu catatan pandemi plesetan dan dagelan mikir [15]. Ia memandang fenomena Covid-19 dengan caranya sendiri melalui celoteh-colotehan kata-kata plesetan sekitar istilah dalam masa pandemi Covid-19 sebagai media hiburan, untuk menjaga imun.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 431
Pembahasan
Tidak jelas siapa yang benar, begitu luar biasa informasi terkait wabah penyakit corona yang menghebohkan dunia. Insan media saling bersautan memberikan informasi terkait pandemi yang melanda penduduk dunia itu, seakan saling adu data satu dengan lainya untuk segera mengiformasikan kepada masyarakat dunia tentang kabar yang sedang viral, yaitu serangan virus mematikan bernama Covid-19. Beragam informasi terkait dengan pandemi virus tersebut. BBC News pada 21 Februari 2020 menginformasikan bahwa kasus corona pertama diketahui pada 31 Desember 2019 yang berasal dari pasar hewan dan ikan laut di Wuhan [16]. Serambinews 26 Januari 2020 memberitakan, jika virus corona diduga akibat kebocoran laboratorium di Kota Wuhan, media ini menulis bahwa laboratorium itu selain tempat pengembangan virus baru, juga diduga merupakan tempat senjata biologi pemusnah masal [17] Merdeka.com pada 27 Januari 2020 menginformasikan jika virus corona berasal dari hewan kelelawar [18]. Sementara Suara.com pada 4 April 2020 menulis bahwa penyebaran virus corona bermula dari pasar basah di Wuhan [19]. Namun Kompas.com menuliskan bahwa asal usul virus korona belum jelas meski media ini melaporkan jika virus corona itu mencuat dipermukaan pada 1 Desember 2019 dan bahwa virus itu tidak berinteraksi dengan pasar sebagaimana pemberitaan media lainnya [20].
Simpang siur pemberitaan Covid-19 terkait dengan kapan, dimana, sebab apa virus corana itu mencuat. Pada bahasan ini sesungguhnya hal itu bukan merupakan suatu yang utama, meskipun kenyataannya menjadi viral di seluruh dunia. Viral sebagai fenomena mencekam, yang menjadikan banyak dari anggota masyarakat dunia mengalami rasa takut dan stress. Padahal rasa takut yang teramat akan berakibat stress dan menjadikan turunnya imun dalam tubuh, sehingga mempermudah virus menyerang tubuh [22]. Dalam sebuah artikel Alodokter memberikan cara memperkuat imun dalam tubuh, di antaranya dengan cara mengelola stress. Stress menurutnya dapat dikendalikan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan agar pikiran dan tubuh rileks. Kelik Pelipur Lara mengobati stress dengan caranya sendiri melalui kata-kata plesetan. Misalnya, istilah Pandemi diplesetkan menjadi Panik dan Deg-degan, hal itu membuat pembaca tertawa dan terasa rileks. Rileks dapat membantu meningkatkan imunitas [15].
432 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa peristiwa Covid-19
dalam pandangan teori ABL [12] dapat berdampak ganda. Yaitu, selain berdampak negatif juga berdampak positif. Karena dalam pandangan teori ABL suatu peristiwa baik sosial maupun budaya ataupun lainnya selalu memunculkan dua peran atau dua hikmah atau dua pelajaran. Sebagaimana kata-kata bijak di balik kesulitan ada kemudahan, di balik musibah ada hikmah, keduanya dapat dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, justru menjadi lebih penting dalam kajian ini ketika peristiwa Covid-19 di jadikan pelajaran untuk mengevaluasi diri. Instruspeksi terhadap perilaku kehidupan sehari-hari sebagai makhluk yang bermartabat, insan yang berbudi, masyarakat yang berakhlak, tiada lain adalah perilaku berbudiutama. Perilaku berbudiutama merupakan tujuan akhir dari pendidikan kebudiutamaan, karena pada hakekatnya kebudiutamaan merupakan nilai luhur dan norma universal, tercermin dalam nilai kemanfaatan (usefulness), kepedulian (philanthropy), kepatuhan (obedience), kepatutan (appropriateness), dan dalam konteks kebangsaan (nasionalism) Indonesia ialah ke-Indonesia-an.
Nilai Kemanfaatan (usefulness)
Istilah kemanfaatan menunjukkan kedekatannya dengan istilah keberartian, kebermaknaan, keberhargaan, kegunaan, keuntungan, dan utilitas serta bertentangan dengan istilah kemudaratan, kerugian, dan kesia-siaan. Secara psikologis, ada dua cakupan arti kebudiutamaan, yaitu; bermanfaat bagi diri sendiri, dan bermanfaat bagi orang lain, dan bila diperluas bermanfaat bagi semesta alam. Bermanfaat bagi diri sendiri berarti bisa membantu diri sendiri. Bermanfaat bagi orang lain berarti bisa membantu orang lain, sedangkan bermanfaat bagi alam berarti bisa memberikan pengaruh baik terhadap kelestarian dan keberlangsungan alam, dalam arti menjaga dari kerusakan alam. Secara singkat, kemanfaatan menunjuk pada kesanggupan seseorang memberikan pengaruh positif dan sumbangan berharga terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan alam. Secara sistemik, salah satu besaran yang biasa digunakan untuk mengukur kemanfaatan atau keuntungan individual (individual rate of return), kemanfaatan atau keuntungan sosial (sosial rate of return), dan belakangan perlu disertakan tolok ukur kemanfaatan atau keuntungan ekologis (ecological rate of return). [14]
Sejalan dengan kaidah tanggungjawab personal, maka setiap orang harus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Artinya, setiap orang harus bermanfaat bagi diri sendiri. Sejalan dengan kaidah tanggungjawab sosial, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 433
bagi manusia lain, maka setiap orang harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam tatanan agama, bahkan telah populer dalam tatanan sosial bahwa bermanfaat bagi banyak orang dipandang sebagai predikat sebaik-baiknya manusia. Sejalan dengan kaidah tanggungjawab universal, maka setiap orang harus bertanggungjawab terhadap lingkungan alam, yang telah diamanatkan tidak hanya untuk kehidupan manusia sekarang, tetapi juga untuk anak cucu hingga akhir jaman. Kemanfaatan sebagai salah satu pilar kebudiutamaan, berarti menjadikan kesanggupan memberikan pengaruh positif dan sumbangan berharga terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan alam [21].
Munculnya Covid-19 berdasar pada informasi berbagai media sebaimana paparan di atas, dipandang sebagai kondisi tidak sejalan dengan prinsip kemanfaatan. ketika tanggung jawab personal, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab universal dilalaikan. Secara personal selayaknya bertanggung jawab terhadap kebersihan dirinya ketika akan dan telah melakukan transaksi dipasar hewan sebagai tempat dimana secara personal dia bekerja. Juga, secara personal bertanggung jawab atas daging hewan yang diperjual belikan. Begitu juga secara sosial, bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada para pelanggan ketika terjadi transaksi, tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan memperhatikan kesehatan pelanggan. Sedangkan secara universal, melalaikan tanggung jawab atas menjaga keseimbangan alam ketika tanpa memperdulikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi layaknya sebagai manusia berbudaya. Oleh karena itu, melalui peristiwa pandemi Covid-19 justru menjadi pressure untuk belajar kebudiutamaan.
Kepedulian (philanthropy)
Istilah kepedulian menunjukkan kedekatan dengan istilah perhatian, kasih sayang, ketertarikan, kesadar-tahuan, kehirauan, ketidakacuhan, keteringatan dan bertentangan dengan keacuhan, ketegaan, kemasa-bodohan, keterlupaan, dan kebencian. Secara psikologis, ada dua cakupan arti kepedulian, yaitu; kehendak memberikan perhatian, kemudah-tersentuhan hati, dan kesediaan mewujudkan keiba-hatian dalam bentuk saling berbagi dan saling membantu. Karena itu kepedulian melibatkan sekaligus kegiatan indera, olah nalar, olah rasa, yang mewujud dalam perilaku ikut memperhatikan, ikut memikirkan, ikut merasakan, dan ikut meringankan setiap ketertinggalan, kesusahan, dan penderitaan orang lain. Secara singkat, menunjuk kepada kesediaan ikut memperhatikan, ikut memikirkan, ikut
434 | New Normal, Kajian Multidisiplin
merasakan, dan ikut meringankan setiap ketertinggalan, kesusahan, penderitaan, serta segala bentuk keadaan tak manusiawi yang dialami atau dihadapi orang lain. Kepedulian sosial tidak hanya tertuju pada penderitaan orang lain, seperti karena kehilangan anggota keluarga, menderita sakit, menjadi korban bencana dan atau kejahatan, tetapi juga tertuju kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti terhadap penyalahgunaan narkoba, tingkat kejahatan dimasyarakat, pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, perusakan fasilitas umum, hingga berbagai perilaku yang mengancam sendi-sendi kehidupan bersama.
Secara praktik-empirik, salah satu tolok ukur kepedulian adalah kesediaan melakukan upaya baik secara perseorangan maupun dalam bentuk tindakan bersama untuk mencegah sedini mungkin berbagai kondisi yang tidak manusiawi dan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, serta kesdiaan untuk mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya demi kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Dengan demikian, kepedulian tidak lain adalah kesediaan setiap orang untuk saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling membantu dalam kebaikan, baik secara jasmani berupa kesehatan dan kesejahteraan, maupun secara rohani berupa ketentraman, kebahagiaan dan kebaikan. Kebahagian dan kebaikan sebagai salah satu unsur utama watak luhur setiap insan. Pandemi Covid-19 disisi lain justru menimbulkan rasa kepedulian sosial. Yaitu peduli terhadap diri sendiri, ketika diri ini memiliki hak hidup yang harus diurus secara baik dan benar. Peduli terhadap masyarakat, ketika masyarakat memerlukan pertolongan, dan peduli terhadap alam semeta, ketika mampu menjaga keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam konteks sosial, perilaku peduli terhadap diri, sesama makhluk, dan alam semesta merupakan keniscayaan. Peristiwa covid-19 menjadi pemicu untuk melakukan kepedulian baik secara pribadi, sesama makhluk maupun alam semesta. Sang Maha Khalik memberikan pelajaran besar terhadap umat manusia melalui wabah penyakit corona.
Kepatuhan (obedience)
Istilah kepatuhan menunjukkan kedekatannya dengan istilah penghormatan, kesalehan, ketaatan, ketundukan, kesetiaan, dan keberbertanggung-jawababan dan ketertiban, yang bertentangan dengan istilah kefasikan, kecongkakan, pemberontakan, pembangkangan, pengkhianatan, dan kekacauan. Scara filosofis, kepatuhan merupakan akibat logis dari kemerdekaan atau kebebasan. Artinya, kepatuhan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 435
merupakan wujud kehormatan dan kemartabatan manusia karena pilihan hidup berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan yang mereka miliki. Karena sebenarnya merupakan akibat logis atau tanggung jawab manusia merdeka, maka sebenarnya kepatuhan sejati tidak bisa dituntut atau dipenuhi oleh manusia terjajah. Jadi kalaupun seorang yang terjajah atau tidak merdeka melakukan suatu tindakan yang sejalan atau tidak sejalan dengan norma atau aturan, maka yang dia lakukan sebenarnya bukan kepatuhan, melainkan keterpaksaan. Sebagai wujud tanggung jawab, kepatuhan tidak bisa dituntut dari siapa pun yang terjajah atau tidak merdeka. Sebagai wujud tanggung jawab, kepatuhan menandai kehormatan atau kemartabatan manusia merdeka. Singkat kalimat, bagi manusia merdeka, tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab, tidak ada kemartabatan tanpa kepatuhan.
Setiap anak manusia lahir memang merdeka. Karena kasih sayang keluarga, mereka bisa tumbuh dan berkembang. Karena keteraturan masyarakat, mereka bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Bisa saja misalnya, seorang anak memilih tetap merdeka, tetapi berarti mereka harus menerima kenyataan, harus bertahan hidup tanpa kasih saying, harus bertahan hidup tanpa jaminan bahwa setelah melaksanakan kewajiaban akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Karena hampir mustahil manusia bisa bertahan hidup dan berkembang secara baik tanpa kasih saying dan sitem penghargaan sosial, maka para ilmuwan sosial menyimpulkan bahwa, berbeda dengan binatang, sejak lahir manusia telah menukar kemerdekaannya dengan kasih sayang dan jaminan keselamatan. Kepatuhan sebagai salah satu pilar kebudiutamaan berarti menjadikan kesediaan untuk secara terhormat tunduk kepada nilai dan norma yang berlaku sebagai konsekuensi logis dari pilihan secara merdeka untuk menjadi anggota suatu kolektivitas sosial, baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, agama, dan Negara.
Uraian di atas merujuk kepada kepatuhan secara sosial, karena menyadari sesadar-sadarnya bahwa untuk mencapai kepatuhan hakiki memerlukan ikhtiar secara maksimal. Melibatkan kerelaan jiwa dan keshalihan sikap dan perilaku, yang menyadari bahwa sebagai makhluk hanya dapat melakukan sebatas ikhtiar. Ada kekuatan luar biasa yang berkuasa terhadap diri dan alam raya yang dapat berkehendak sesuai kodrat irodat-Nya. Seperti peristiwa Covid-19, dipandang dalam kacamata kepatuhan merupakan cara penguasa jagad raya (Khalik) mengingkatkan bahkan membelajarkan untuk bertindak peduli. Tidak
436 | New Normal, Kajian Multidisiplin
saja secara pribadi, sesama insan manusia juga peduli terhadap alam semesta.
Kepatutan (appropriateness)
Istilah kepatutan menunjuk kedekatannya dengan istilah kepantasan, kewajaran, kesogyaan, ketepatan, kebenaran, keselarasan, keserasian, kesesuaian, kesantunan, kecocokan, kesejalanan, kecukupan, ketertiban, kesetimpalan, dan kesetimbangan, dan bertentangan dengan istilah kemencengan, penyimpangan, kesalahan, kemlesetan, penye-lewengan, kekotoran, morat-marit, compang-camping, carut-marut, dan kacau-balau. Istilah patut (proper) sering dihadirkan secara bersama dengan istilah sesuai (fit), seperti dalam ungkapan uji kepatutan dan kesesuaian. Kepatutan tidak hanya menunjuk pada kesesuaian antara kedudukan dengan peran, tetapi juga antara perilaku dengan situasi dan kondisi. Kedudukan adalah letak atau posisi seseorang dalam suatu lapisan atau keragaman sosial, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan-nya. Ada beberapa kemungkinan sehubungan kesesuaian kedudukan dengan peran. Kemungkinan pertama adalah disfungsional, karena seseorang justru secara sengaja melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kedudukannya. Kemungkinan kedua adalah malfungsional, karena seseorang tanpa sengaja melakukan sesuatu yang akibatnya tidak sejalan dengan perannya. Kemungkinan ketiga adalh unfungsional, karena seseorang tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kedudu-kannya. Kemungkinan keempat adalah fungsional, karena seseorang telah melakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya, serta memberi-kan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Bertutur dan bertindak menurut nilai kepatutan berarti berbicara dan berperilaku sesuai dengan kedudukan dan peran yang diharapkan. Bila dikaitkan dengan konsep kesesuaian, maka kepatutan juga berperilaku, berbusana, berbicara, dan bertingkah laku sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan tempat dan waktunya. Tidak patut dan disfungsional, misalnya bila seseorang melakukan penipuan dan pemalsuan. Seorang dosen seperti seorang ilmuwan boleh berbuat kesalahan tapi tidak boleh berbohong untuk kepentingan pribadi, apalagi menipu untuk maksud jahat. Pemalsuan adalah salah satu bentuk penipuan bersifat publik. Memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang, misalnya tidak hanya perbuatan jahat bagi pihak yang dipalsukan, tetapi juga berbuat jahat bagi pihak yang menerima dan mempercayai berkas bertanda-tangan palsu. Kepatutan adalah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 437
kesesuaian antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang dijalankan, kesesuaian antara perilaku dengan situasi dan kondisi, serta antara perilaku dengan tempat dan waktu. Secara lebih singkat, kepatutan mencakup bukan sekedar kepatuhan kepada aturan hukum, terutama yang tertulis, tetapi juga memenuhi kreteria kebermoral, kesantuanan, dan keelokan yang tidak tertulis. Perilaku patut berarti tindak dan tutur yang tidak hanya bernilai tujuan baik, tetapi juga dilakukan dengan cara yang baik, serta gaya yang santun. Kepatutan sebagai pilar kebudiutamaan, berarti menjadikan kebiasaan bertindak bertutur dan berbusana dengan niat baik, dengan cara yang baik, dengan gaya yang santun.
Covid-19 merupakan peristiwa yang membelajarkan untuk mengubah peyimpangan budaya kodrati Illahiyah. Budaya tertib, budaya santun, budaya hormat, budaya peduli dan budaya budaya sosial lainnya yang telah terabaikan secara masif. Melalui pandemik Covid-19 budaya-budaya itu mulai terimplementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yang harus dipaksa melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat. Seperti, istilah pembatasan total (lockdown), PSBB, PSSM dan New Normal semua adalah dalam rangka mendidik berlaku patuh, patut, peduli, manfaat menuju perilaku berbudiutama.
Keindonesiaan (nasionalism)
Nasionalism konteks Indonesia kemudian disebut Ke-Indonesia-an, maknanya tentu berhubungan langsung dengan kata Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara. Indonesia adalah bangsa bernegara. Sebagai bangsa bernegara, warga Negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai Negara, warga Negara Indonesia berpegang pada pancasila sebagai dasar Negara. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, wawasan nusantara sebagai cara pandang atas hubungan daerah-daerah, hubungan antar daratan dan lautan, dan hubungan antar kebhinekaan suku bangsa, Bahasa daerah, kebudayaan dan adat istiadat daerah sebagai satu kesatuan, bangsa Negara Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya mengamanatkan Negara, bangsa dan masyarakat dan setiap warga Negara Indonesia untuk tidak hanya meningkatkan mutu kesalehan ritual-pesonal, tetapi juga kesalehan etik-sosial, serta menghargai kemajemukan keyakinan dan agama yang dianut bangsa Indonesia. Harus selalu diingat, menjadi bangsa Indonesia adalah takdir yang kita sama sekali tidak bisa memilihnya, sedangkan menjadi umat beragama tentu adalah pilihan merdeka dan penuh tanggung jawab.
438 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Sungguh sila Ketuhanan yang Maha Esa lebih dari sekedar plurarisme keberagaman, yang hanya mengakui hak berbeda agama tanpa kewajiban meningkatkan mutu keberagaman.
Kemanusiaan yang adil dan beradab mengamanatkan kepada Negara, bangsa dan masyarakat dan setiap warga Negara Indonesia untuk tidak hanya mengakui manusia sebagai makhluk paling sempurna, makhluk yang memiliki cipta, rasa dan karsa, namun juga mengakui kemerdekaan sekaligus kesetaraan dan keadilan di antara mereka, serta mengembangkan peradaban dan keberadaban manusia. Sungguh kemanusiaan yang adil dan beradab lebih dari sekedar filsafat serta nilai-nilai humanism. Persatuan Indonesia mengamanatkan keutuhan tetapi juga kesatuan bangsa, wilayah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah persatuan menegaskan adanya bagian-bagian (parts) yang membentuk satu kesatuan dan keutuhan (unity and wholeness). Ini berarti bahwa setiap komponen bangsa harus menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kesatuan, yang karena itu harus ikut ambil bagian (give part) kepada masing-masing komponen, sehingga berlangsung hubungan timbal-balik yang adil antara sumbangan dengan pembagian (contribution and distribution). Persatuan Indonesia lebih dari sekedar nasionalisme yang hanya menuntut pengorbanan bagi bangsa-bangsa tanpa penghargaan kembali kepada komponen bangsa Negara. Harus ada kepastian bahwa kebersamaan dalam ke Indonesia-an bisa memberikan nilai kebaikan umum (public goods) lebih tinggi dari pada apa yang bisa dicapai secara sendiri-sendiri oleh komponen bangsa. Tanpa kesetaraan, keadilan dan kemanfaatan lebih tinggi, persatuan Indonesia tak lebih dari penindasan dan penjajahan dalam bentuk berbeda.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan mengamanatkan kepada Negara, bangsa dan masyarakat dan setiap warga Negara Indonesia untuk menempatkan hikmah kebijaksanaan sebagai nilai utama dalam menetapkan pimpinan rakyat sekaligus apa yang harus dilakukan oleh pemimpin rakyat dan dilaksanakan dalam bentuk permusyawaratan atau perwakilan. Secara filosofis, hikmah (lesson) merupakan puncak dari segala pengetahuan. Kalau pengetahuan bersangkut paut dengan kebenaran dan kesalahan logis-empati (tru and fals), maka hikmah atau pelajaran bersangkut paut dengan kebenaran dan kesalahan moral-etik (right and wrong). Sungguh merupakan kesia-siaan bila manusia hanya berasil memperoleh pengetahuan tetapi gagal mendapatkan pelajaran, karena justru pelajaran
New Normal, Kajian Multidisiplin | 439
yang berguna bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Kepemimpinan yang baik menurut pancasila bukan hanya diukur berdasarkan hanya pada kemampuannya memenuhi atau mengikuti kehendak semua atau kehendak kebanyakan (will of all or will of majority) sebagaimana dalam demokrasi. Tanpa kendali hikmah kebijaksanaan, demokrasi hanya akan melahirkan etika dan tirani mayoritas.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kepada Negara, bangsa dan masyarakat dan setiap warga Negara Indonesia untuk tidak mengedapankan nilai-nilai keadilan menurut hukum, tetapi nilai-nilai keadilan menurut etika sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum berarti memberikan perlakuan sesuai dengan perbuatan dalam arti perbuatan salah dan buruk mendapatkan hukuman, sedangkan perbuatan benar dan baik mendapatkan ganjaran. Berbeda dari nilai keadilan hokum yang membagi manusia menjadi kelompok benar-baik dan kelompok salah-buruk, maka nilai keadilan sosial membagi manusia menjadi kelompok ekonomi mampu atau beruntung dan kelompok ekonomi lemah dan atau tak beruntung. Negara yang berkeadilan sosial, karena itu berkuwajiban mendahulukan kelompok ekonomi lemah atau tak beruntung sebagai yang pertama mendapatkan bantuan agar bisa mandiri dan berkembang secara berkelanjutan. Pun begitu berkenan dengan kewajiban ekonomi terhadap Negara seperti pajak secara seimbang. Artinya, sesuai asas keadilan sosial apabila kelompok ekonomi mampu dan beruntung memberikan kontribusi lebih besar agar Negara bisa membelanjakan anggaan lebih besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat ekonomi lemah dan kurang beruntung. Pada tingkat perseorangan sikap yang harus dikembangkan adalah kesadaran untuk mendudkung tidak saja penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat demi keadilan sosial. Indonesia akan menjadi taman yang indah dan membahagiakan bagi semua warga negaranya apabila dihiasi oleh ilmu kaum cendekia, keadilan pejabat pemerintah, kedermawanan kaum hartawan, kejujuran para pengusaha, kerja keras para pekerja, dan usaha serta do’a sepenuh keyakinan kaum miskin. Peristiwa pandemi Covid-19 menjadi pemicu dan memotivasi untuk meningkatkan perilaku nasionalism.
Penutup
Secara ringakas ringkas kajian dalam bookchapter yang berjudul Covid-19: Perilaku berbudiutama merupakan sisi lain cara pandang terhadap suatu persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Bahwa tidak Tuhan telah memberikan soal sekaligus memberikan jawab, memberikan
440 | New Normal, Kajian Multidisiplin
masalah sekaligus solusi, hanya saja tergantung bagaimana dapat mengambil pelajaran dari fenomena atau peristiwa itu. Ketika tinjauan terhadap suatu peristiwa dari sudut pandang negatif, maka akan didapat ganjaran dari prasangkanya itu. Oleh karena itu melalui tulisan ini kita belajar dari sudut pandang postif berharap menghasilkan nilai postif.
Menutup uraian ringkas tentang nilai-nilai kebudiutamaan ini, ada baiknya menyimak sebuah ungkapan sangat bijaksana tentang betapa penting perihal watak baik bagi manusia. When wealth is lost, nothing is lost, When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Artinya, ketika kekayaan hilang, tiada sesuatu pun hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Ketika watak baik hilang, segalanya hilang. Semoga kita semua terhindar dari sekedar kehilangan kekayaan walaupun sebenarnya bisa dicari kembali, terhindar dari sekedar kesehatan yang merupakan prasyarat bagi segala nikmat yang lain, dan yang lebih penting lagi tidak pernah kehilangan watak baik yang menjadi pembeda ntara manusia dengan makhluk hidup lain.
Rujukan
[1] M. I. Ilmie, Bertahan di Wuhan; Kesaksian Wartawan Indonesia di Tengah Pandemi Corona, Jakarta: Pustaka Utama, 2020.
[2] Merdeka.com, "Fakta-fakta Wuhan Jadi Kota Mati Akibat Virus Corona," 28 Januari 2020. [Online]. Available: http;//m.merdeka.com. [Accessed 28 Januari 2020].
[3] Kompas.com, "Divertova, Italia, Dampat Covid-19 Lebih Buru dari Perang Dunia II," 26 Maret 2020. [Online]. Available: https://kompas.com. [Accessed 26 Maret 2020].
[4] Tribunnews.com, "Jumlah Pasien Virus Corona Dunia, Indonesia Peringkat 31," 14 Juni 2020. [Online]. Available: https://jogja.tribunnews.com. [Accessed 14 Juni 2020].
[5] Malang-post.com, "Terapkan Ganjil Genap Genap di Kabupaten Malang," 2 Juni 2020. [Online]. Available: https://www.malang-post.com. [Accessed 2 Juni 2020].
[6] Republika.co.id, "Ta'awun Sosial Atasi Dampak Ekonomi Covid-19," 24 April 2020. [Online]. Available: http://republika.co.id. [Accessed 24 April 2020].
[7] B. News, "Covid-19: Indonesia Berpotensi Terdampak Ekonomi Jauh Lebih Berat Ketimbang Krisis Moneter," 24 Juni 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 441
[Online]. Available: https://www.bbc.com. [Accessed 24 Juni 2020].
[8] Kompas.id, "Model Pembelajaran Saat Pandemi Covid-19," 9 Juni 2020. [Online]. Available: https://kompas.id. [Accessed 9 Juni 2020].
[9] M. W. Khan, Muhammad Nabi untuk Semua. Pengantar Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2005.
[10] Al-Quran, Ar-Rum:30.
[11] Al-Quran, Al-Anbiya: 107.
[12] Rochsun, Spirit Aclak, Bingkak, dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi Dalam Masyarakat Using Kontemporer, Yogyakarta: Bildung, 2020.
[13] A. Blog-BlogSalad, "4 Pilar Pendidikan Menurut Unesco," 2020. [Online]. Available: http://atikatikaaz.blog.
[14] R. F. White, "The Principle of Utility," [Online]. Available: http://faculty.msj.edu/whiter/UTILITY.thm. [Accessed 25 April 2019].
[15] K. P. Lara, Speakerrman Stop Stress, Sleman Yogyakarta: CV Prineka, 2020.
[16] B. News, "Siapa Orang Pertama yang Memicu Wabah Virus Corona dan Mengapa Orang ini Harus Ditemukan," 2020. [Online]. Available: https://bbc.com. [Accessed 26 Januari 2020].
[17] Tribunnews.com, "Apa Penyebab Corona Sangat Mengerikan? Terbongkar Dugaan Kecerobohan China, Virus Bocor dari Lab.," 2020. [Online]. Available: https://aceh.tribunnews.com. [Accessed 26 Januari 2020].
[18] Merdeka.com, "Dari Pasar Wuhan Hingga Kepanikan Global, Kronologi Penyebaran Virus Corona," 2020. [Online]. Available: https://m.merdeka.com. [Accessed 27 Januari 2020].
[19] Suara.com, "Dari China, Begini Awal Penyebaran Virus Corona Keseluruh Dunia," 2020. [Online]. Available: https://suara.com. [Accessed 4 April 2020].
[20] Kompas.com, "Virus Corona Ternyata Tak Berasal dari Pasar Seafood Wuhan, Ini Faktanya," 2020. [Online]. Available: https://kompas.com. [Accessed 2020 Februari 2020].
442 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[21] J. Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London: ERRATA, 1780.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 443
Bab 28
Peningkatan Kepuasan Kerja Berbasis Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Nurul Qomariah dan M. Sulton32
Pengantar
Pada saat ini kita berada pada abad ke 21, tantangan yang langsung dihadapi adalah globalisasi dengan segala implikasinya. Agar organisas i ba i k pe merin tah maupun s wasta tetap eksis maka harus berani menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi supaya dapat memenangkan persaingan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimun apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang baik. Karyawan akan bekinerja dengan baik jika merasa puas dalam bekerja. Oleh karena itu semua organisasi atau badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta harus memperhatikan kepuasan kerja dari karyawannya. Kepuasan kerja ini merupakan factor penting yang perlu diperhatikan. Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang akan pekerjaan yang diterimanya [1].
Karyawan yang merasa puas dalam bekerja akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kepuasan kerja ini merupakan sikap dari seseorang terhadap pekerjaannya [2]. Banyak factor yang dapat meningkatkan kepuasan kerja seseorang dalam bekerja. Beberapa factor yang disinyalir dapat meningkatkan kepuasan kerja antara lain: motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi. Factor pertama yang dapat meningkatkan kepuasan kerja adalah motivasi kerja seseorang. Motivasi kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kepegawaian sebuah organisasi atau lembaga, karena dengan memiliki motivasi yang kuat maka para pegawai akan giat bekerja. Pegawai dengan motivasi kerja yang tinggi akan melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan [3]. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual [4]. Motivasi kerja yang rendah atau kurang baik akan merugikan organisasi, karena dengan motivasi kerja yang rendah pencapaian tujuan lembaga akan tertunda. Oleh
32 Dr.Nurul Qomariah dan Dr. M. Sulton, Universitas Muhammadiyah Jember
444 | New Normal, Kajian Multidisiplin
karena itu motivasi kerja merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki pegawai. Motivasi kerja adalah sebuah dorongan pada diri pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan [5]. Motivasi kerja adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan dan memelihara perilaku manusia kearah pencapaian suatu tujuan [6]. Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya nya untuk mencapai kepuasan [7]. Dari beberapa pendapat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa motivas kerja merupakan dorongan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan atau kepuasan. Motivasi kerja karyawan tidak selamanya berada dalam kondisi baik, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi kerja di saat motivasi kerja pegawai menurun. Meningkatkan motivasi kerja pegawai bisa dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pegawai serta menghargai hasil dari pekerjaan mereka. Terdapat dua macam cara d a l a m meningkatkan motivasi k e r j a k a r y a w a n , yaitu motivasi langsung dengan memenuhi kebutuhan pegawai secara material dan non material serta motivasi tidak langsung dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pekerjaan.
Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai menurut Herzberg dalam teori dua faktornya terdiri dari dua macam faktor. Faktor pertama adalah motifation factor atau daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing pegawai, faktor kedua adala hygieni factor berupa daya dorong yang datang dari luar diri pegawai, terutama dari organisasi/lembaga tempatnya bekerja. Daya dorong dari luar diri pegawai bentuknya bisa berupa kompensasi yang diterima dan lingkungan kerja sebagai penunjang saat bekerja. Menurut teori jika seseorang mempunyai motivasi yang kuat dalam bekerja maka para pegawai ini kan merasa puas dengan pekerjaan yang dihadapinya. Teori X ini untuk memotivasi pegawai hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi pegawai, kerjasama dan keterkaitan pada keputusan. Jenis motivasi yang diterapkan adalah motivasi positif. Untuk itu seorang kepala sekolah dituntut konsisten dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan bersama dan menggalang partisipasi bawahan [8]. Perilaku yang timbul pada diri seseorang dalam rangka motivasi sebagai konsep manajemen, didororng oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan yang ada pada diri seseorang mendorong seseorang perilaku.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 445
Sikap perilaku seseorang selalu berorientasi pada tujuan yakni terpenuhnya kebutuhan yang diinginkan. Setiap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam organisasi, pasti dalam rangka terwujudnya suatu kepuasan. Beberapa penelitian tentang hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja sudah banyak dilakukan.
[9] dalam penelitiannya dengan tema gaya kepemimpinan dan motivasi yang dikaitkan dengan kepuasan pada obyek karyawan Politeknik Negeri Padang dimana hasilnya adalah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja. [10] dalam penelitian dengan tema kompetensi SDM dan motivasi kerja jika dihubungkan dengan kepuasan kerja karyawan pada Sekretariat DPRK yang ada di Bireuen Provinsi Aceh. Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan antara lain bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan pengaruh motivasi yang signifikan terhadap kepuasan kerja. [11] melakukan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan tema motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi yang dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan pada
PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, [12] dalam penelitiannya dengan tema motivasi dan kompetensi SDM jika dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi kerja berdampak positif terhadap kepuasan kerja. [13] dalam penelitiannya yang dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan tema karakteristik individu, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi kaitannya dengan kepuasan kerja. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh karakteristik individu, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. [14] dalam penelitiannya dengan tema motivasi dan budaya organisasi jika dikaitkan dengan kepuasan kerja pada karyawan Rumah Sakit Umum (RSU) Salatiga yang berjumlah 621 karyawan dengan sampel 86 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. [15] melakukan penelitian dengan tema kepemimpinan, motivasi dan religiusitas yang dihubungkan dengan kepuasan kerja karyawan pada PT. Unza Vitalis Salatiga. Hasilnya antara lain bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
Faktor berikutnya yang juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam bekerja adalah gaya kepemimpinan. Faktor penting yang menentukan kinerja karyawan dan kemampuan organisasi
446 | New Normal, Kajian Multidisiplin
beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah kepemimpiman. Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin (follower) dan bagaimana seseorang pemimpin meng-arahkan follower akan menentukan sejauh mana follower mencapai tujuan atau harapan pimpinan. Konsep kepemimpinan yang berkem-bang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan (leadership) yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal jadi kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi [7]. Kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi karyawan agar supaya karyawan bekerja kearah pencapaian tujuan organisasi yang sudah dicanangkan [16]. Biasanya pemimpin mempunyai efek yang berarti pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang di bidang manajemen.
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran [8].Masalah kepemimpinan ini telah muncul bersamaan dengan diawalinya sejarah tentang manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan dari pada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dbentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu. Dalam suatu organisasi selalu dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat membawa bahtera organisasi menuju tujuan yang sudah direncankan saat awal organisasi didirikan. Keberadaan pempinan dalam suatu organisasi menjadi masalah yang urgen sekali, pemimpin harus mampu menggerakkan sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi agar beerja lebih baik dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Keberadaan pemimpin ini sangat berdampak terhadap kepuasan kerja dari karyawan. Pemimpin yang bersifat adil dan bijaksana biasanya akan dapat menggerakkan anak buahnya untuk bekerja lebih baik. Banyak penelitian tentang kepemimpinan yang dihubungkan dengan kepuasan kerja karyawan.
[15] menyatakan dalam penelitiannya dengan kepemimpinan yang dihubungkan dengan kepuasan kerja yang hasilnya adalah kepemimpian yang bijaksana dapat meningkatkan kepuasan kerja pada
New Normal, Kajian Multidisiplin | 447
PT. Unza Vitalis Salatiga Jateng. [13] juga melakukan penelitian yang menghubungkan kepemimpinan dengan kepuasan kerja pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang hasilnya adalah kepemimpinan dapat meningkatkan kepuasan kerja. [9] dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan karyawan Politeknik Negeri Padang. [11] menyatakan bahwa kepemimpina mempunyai dampak negative terhadap kepuasan kerja karyawan. [17] dalam penelitiannya menya-takan bahwa kepemimpinan berdampak terhadap kepuasan kerja karyawan kator SAR Sorong. [18] dalam penelitiannya dengan tema gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja pada karyawan administratif di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan populasi sebanyak 404 responden dan diambil sebagai sampel 100 karyawan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. [19] dengan tema penelitian motivasi, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan tyang dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan dengan jumlah responden sebanyak 46 responden. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.
Faktor berikutnya yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dikenal luas sebagai fondasi sistem dan aktifitas manajemen dalam setiap organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisai sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi.
Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang didalam organisasi. Dengan demkian maka budaya organisasi merupakan jiwa para anggota organisasi.Budaya organisasi dipandang sebagai nilai nilai bersama dan norma-norma perilaku yang diyakini dan dianut oleh anggta organisasi [8]. Nilai dan norma perilaku tersebut menciptakan pendekatan yang digunakan anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. [20] menyatakan budaya organisasi adalah suatu pola dari
448 | New Normal, Kajian Multidisiplin
nilai-nilai dan kepercayaan bersama yang memberi makna dan peraturan dalam bertingkah laku anggota oganisasi. Nilai-nilai ini melengkat pada visi organisasi dan anggota-anggotanya dalam menetapkan peluang dan rencana strategis. Seperti kepriadian yang membentuk seorang individu, budaya organisasi membentuk respon anggota-anggota organisasi dan menetapkan apa yang akan atau bisa dilakukan.
Banyak pakar menyebutkan bahwa budaya organisasi dapat menjadi basis adaptasi dan kunci keberhasilan organisasi sehingga banyak penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai atau norma-norma perilaku yang bisa memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan organisasi. Namun demikian, relatif sedikit yang mencoba menghubungkan budaya organisasi dengan variabel variabel sumber daya manusia yang penting, khusus nya kinerja karyawan. Pada masa lalu, budaya organisasi dipandang sebagai sesuatu yang tunggal (unitary) dalam perpektif monolitik, sehingga suatu organisasi dikatakan mempunyai strong culture jika terdapat nilai dan norma perilaku yang terintregasi, homogen, stabil, dan dianut oleh seluruh anggota organisasi. Norma-norma dan perilaku dalam suatu organisasi akan berdampak terhadap perilaku kerja seorang karyawan.
Norma-norma dan aturan biasanya sudah ditanamkan dan disosialisasikan pada karyawan saat karyawan baru masuk dalam organisasi tersebut, sehingga norma-norma itu akan melekat dalam pikiran dan perilaku karyawan. Norma-norma yang baik akan membekas jika disertai dengan suri tuladan dari para pimpinan. Norma yang baik dan posisitf akan meningkatkan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya. Pekerjaan yang selesai dengan tepat waktu menandakan bahwa karyawan itu puas dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menurut interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal sarupa lainnya. Ini berarti penilaian (assesment) seorang karyawan terhadap puas atau tidak puasnya dia terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang diskrit (terbedakan dari terpisahkan satu sama lain). Oleh karena itu budaya organisasi ini erat sekali kaitannya dengan kepuasan kerja seseorang. Beberapa penelitian tentang budaya organisasi sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 449
[14] dalam penelitiannya dengan tema motivasi dan budaya organisasi kaitannya dengan kepuasan kerja pada karyawan rumah sakit dengan responden 86 karyawan yang hasilnya bahwa budaya kerja yang baik ternyata dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. [13] melakukan penelitian pada pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan responden sebanyak 326 responden dan hasilnya adalah bahwa budaya organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. [21] dalam penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. [22] melakukan penelitian dengan tema kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompensasi jika dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan Pada PT Kautsar Utama Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signify-kan terhadap kepuasan kerja karyawan baik secara parsial maupun simultan.
Dinas Sosial Kabupaten Jember, ditetapkan berdasarkan N omor 48 tahun 2008 sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomer 15 tahun 2008, adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang sosial. Dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada B upati melalui Sekretaris Kabupaten. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya didalam teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Namun demikian dalam upaya menciptakan kinerja kerja karyawan pada Dinas Sosial Kabupaten Jember, nampaknya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang belum ideal masih ada di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dimana masih ada kendala lain diantaranya, karyawan yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik antar individu maupun kelompok, karyawan yang datang kerja terlambat, dan tidak masuk kerja tanpa ijin. Sehingga mengakibatkan kinerja karyawan menurun yang disebabkan karyawan yang selalu membuat kesalahan dan motivasi karyawan yang rendah dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga pekerjaan karyawan tidak dapat terselesaikan seuai dengan yang direncanakan.
Dari latar belakang yang berisi teori dan penelitian terdahulu serta permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Jember maka pertanyaan penelitian yang perlu diutarakan adalah bagaimana caranya agar kepuasan kerja yag ada di Dinas Sosial Kabupaten Jember
450 | New Normal, Kajian Multidisiplin
meningkat jika dihubungkan dengan variable motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis motivasi kerja, kepemimpnan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember.
Pembahasan
Karakteristik Responden
Hasil statistic deskriptif berdasarkan jenis kelamin maka diperoleh data bahwa dari 32 responden yang dijadikan sampel pada Dinas Sosial Kabupaten Jember, sebagian besar responden adalah laki-laki yakni sebanyak 17 (53,1%) orang dan perempuan berjumlah 15 (46,8%) orang. Hasil analisis statistic deskriptif dengan usia sebagai indicator maka dari 32 responden, sebagian besar responden berada dalam rentang usia 20-35 tahun yakni sebanyak 1 orang (3,1%), sedangkan yang berada dalam rentang usia 35-45 tahun sebanyak 5 orang (15,6%), dan responden berada dalam rentang usia > 45 tahun sebanyak 26 responden (81,2%).
Berdasarkan tabulasi analisis statistic deskriptif terkait dengan responden berdasarkan jenjang pendidikan maka diperoleh data bahwa dari 32 responden, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD yakni sebanyak 3 orang (9,3%), yang memiliki pendidikan terakhir SLTA/Sederajat yakni sebanyak 3 orang (9,3%), yang memiliki pendidikan terakhir Diploma yakni sebanyak 1 orang (3,1%), yang memiliki pendidikan terakhir S1 yakni sebanyak 21 orang (65,6%), dan yang memiliki pendidikan terakhir S2 yakni sebanyak 4 orang (12,5%).
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Untuk variable motivasi kerja maka dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentantang pernyataan “Perusahaan memberi-kan gaji yang sesuai dengan kinerja kerja saya”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral, 20 responden (62,5%) menyatakan setuju, 12 responden (37,5%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang perusahaan memberikan gaji yang sesuai dengan kinerja kerja. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Perusahaan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bekerja kepada saya”, tidak ada responden yang menyatakan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 451
sangat tidak setuju, tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan netral, 25 responden (78,1%) menyatakan setuju, 6 responden (18,8%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang perusahaan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bekerja.
Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya mampu berinteraksi dan bisa diterima dalam kelompok kerja”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 3 responden (9,4%) menyatakan netral, 19 responden (59,4%) menyatakan setuju, 9 responden (28,1%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang mampu berinteraksi dan bisa diterima dalam kelompok kerja. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pimpinan memberikan perhatian dan penghargaan terhadap prestasi kerja saya”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 8 responden (25%) menyatakan netral, 17 responden (53,1%) menyatakan setuju, 6 responden (18,8%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pimpinan memberikan perhatiandan penghargaan terhadap prestasi kerja saya.
Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Fasilitas penunjang yang ada ditempat kerja saudara sesuai dengan yang diinginkan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 2 responden (6,3%) menyatakan tidak setuju, 1 responden (3,1%) meyatakan netral, 14 responden (43,8%) menyatakan setuju, 15 responden (46,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang fasilitas penunjang yang ada ditempat kerja saudara sesuai dengan yang diinginkan.
Berdasarkan analisis statistic deskriptif tentang variable kepemim-pinan maka dapat dijelaskan responden berdasarkan item-item pernya-taan kepemimpinan (X2) dapat dijelaskan dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pemimpin Bapak/Ibu harus membina komunikasi yang baik dengan bawahan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 2 reponden (63%) menyatakan netral, 14 responden (43,8%) menyatakan setuju, 15 responden (46,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden
452 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menilai setuju tentang pernyataan pemimpin Bapak/Ibu harus membina komunikasi yang baik dengan bawahan. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pemimpin Bapak/Ibu harus paham apa yang diharapkan dari pegawai pada saat melakukan penugasan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 2 responden (6,3%) menyatakan netral, 17 responden (53,1%) menyatakan setuju, 13 responden (40,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan pemimpin Bapak/Ibu harus paham apa yang diharapkan dari pegawai pada saat melakukan penugasan.
Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pemimpin Bapak /Ibu harus peduli terhadap tugas karyawan lain sebagai dari tanggung jawabnya”, tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral, 20 responden (62,5%) menyatakan setuju, 12 responden (37,5%) menyatakan setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan pemimpin Bapak/Ibu harus peduli terhadap tugas karyawan lain sebagai dari tanggung jawabnya. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pemimpin Bapak/Ibu harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan mengenai pemberlakuan hukuman bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan”, tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral, 19 responden (59,4%) meyatakan setuju, 13 responden (40,6%) menyatakan setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan pemimpin Bapak/Ibu harus bertindak tegas dalam mengambil keputusan mengenai pemberlakuan hukuman bagi karyawan yang melanggar peraturan peruusahaan. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Pemimpin mempunyai inisiatif yang tinggi dalam memberikan ide untuk meningkatkan hasil kerja”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral, 20 responden (62,5%) menyatakan setuju, 12 responden (37,5%) menyatakan setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar reseponden menilai setuju tentang pernyataan pemimpin mempunyai inisiatif yang tinggi dalam memberikan ide untuk meningkatkan hasil kerja.
Untuk variable budaya organisasi maka dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan perusahaan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 453
netral, 18 responden (56,3%) menyatakan setuju, 14 responden (43,8%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan perusahaan. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan netral, 20 responden (62,5%) menyatakan setuju, 11 responden (34,4%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan netral, 24 responden (75%) menyatakan setuju, 7 responden (21,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya selalu berusaha menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan.
Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi dalam pekerjaan yang beresiko”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 5 responden (15.6%) menyatakan netral, 18 responden (56,3%) menyatakan setuju, 9 responden (28,1%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi dalam pekerjaan yang beresiko. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Dalam melakukan tugas saya mengerjakan pekerjaan dinas terlebih dahulu dari pada pekerjaan pribadi”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan netral, 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 14 responden (43,8%) menyatakan setuju, 17 responden (53,1%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan dalam melakukan tugas saya mengerjakan pekerjaan dinas terlebih dahulu dari pada pekerjaan pribadi.
Untuk variabel kepuasan kerja maka dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Perusahaan memberikan
454 | New Normal, Kajian Multidisiplin
gaji sesuai dengan kinerja kerja saya”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral, 17 responden (53,1%) menyatakan setuju, 15 responden (46,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan perusahaan memberikan gaji sesuai dengan kinerja kerja saya. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya merasa aman dan nyaman selama bekerja”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral, 22 responden (68,8%) menyatakan setuju, 10 responden (31,3%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya merasa aman dan nyaman selama bekerja. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Manajer diperusahaan ini memberikan dukungan kepada saya”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan netral, 21 responden (65,6%) menyatakan setuju, 10 responden (31,3%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan manajer diperusahaan ini memberikan dukungan kepada saya.
Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Perusahaan selalu memberikan pengawasan yang tepat bagi para karyawan”, tidak ada respon yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, 3 responden (9,4%) menyatakan netral, 14 responden (43,8%) menyatakan setuju, 15 responden (46,9%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan perusahaan selalu memberikan pengawasan yang tepat bagi para karyawan. Dari 32 responden yang memberikan tanggapan tentang pernyataan “Saya dan rekan kerja yang lain menjalin komunikasi dengan baik”, tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan tidak setuju, 1 responden (3,1%) menyatakan netral, 17 responden (53,1%) menyatakan setuju, 13 responden (40,6%) menyatakan sangat setuju. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menilai setuju tentang pernyataan saya dan rekan kerja yang lain menjalin komunikasi dengan baik.
Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data
Uji validitas merupakan alat untuk mengukur sah atau tidak nya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil uji validitas data menunjukkan bahwa korelasi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 455
antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang valid. Karena r hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Uji reliabilitas merupakan uji data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup atau memenuhi kriteria, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: motivasi kerja (X1), kepemimpinan (X2), dan budaya organisasi (X3) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan kerja (Y). Adapun persamaan regresi linier berganda dari hasil penelitian adalah: Y = 2,620+0,244+0,408+0,238+2,992.
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Hasil penelitian telah membuktikan terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Melalui hasil yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,232 > 1,701 dengan taraf signifikan 0,034 < 0,05 dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa karyawan yang mempunyai motivasi bekerja yang tinggi maka mereka akan mersakan kepuasan dalam bekerja.
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Melalui hasil yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,877 > 1,701 dengan taraf signifikan 0,008 < 0,05 dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara parsial variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan
456 | New Normal, Kajian Multidisiplin
itu harus dapat memberikan suri tauladan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan tidak terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Melalui hasil yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,550 > 1,701 dengan taraf signifikan 0,132 < 0,05 dengan demikian maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara parsial variabel budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa walaupun budaya organisasi yang telah ditanamkan oleh perusahaan secara baik dan diterapkan ternyata tidak dapat meningkat-kan kepuasan kerja karyawan.
Penutup
Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan adanya pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi motivasi kerja yang diberikan maka dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan hipotesis penelitian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan adanya pengaruh antara kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan yang baik, mampu mengarahkan dan membimbing bawahannya dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan hipotesis penelitian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan tidak adanya pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya budaya organisasi yang diterapkan di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan hipotesis penelitian maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan adanya pengaruh antara motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan hipotesis penelitian maka Ho diterima dan Ha ditolak.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 457
Rujukan
[1] M. N. Azhad, Anwar, eta N. Qomariah, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jember: Cahaya Ilmu, 2015.
[2] A. A. A. P. Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kedua. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2010.
[3] H. Simamora, Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Sekolah. Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2006.
[4] S. Robbins, Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat, 2011. [5] V. Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. [6] E. Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia(Cetakan ke tujuh).
Jakarta: Salemba Empat, 2015. [7] M. S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi.
Jakarta: Bumi Aksara, 2016. [8] S. Robbins eta T. A. Judge, Perilaku Organisasi, Organizational
Behaviour. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2008. [9] F. Wirda eta T. Azra, «Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional
dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja karyawan Politeknik Negeri Padang», Polibisnis, libk. 4, zenb. 1, or. 24–33, 2012.
[10] M. Yusuf, «PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVAI STERHADAP KEPUASAN KERJA APARATUR», J. Kebangs., libk. 4, zenb. 8, or. 1–11, 2015.
[11] I. Ayu eta A. Suprayetno, «Pengaruh Motivasi Kerja , Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan ( Studi kasus pada PT . Pei Hai International Wiratama Indonesia )», Jurn, zenb. 1996, or. 124–135, 2005.
[12] F. Adam eta J. Kamase, «The effect competence and motivation to satisfaction and performance», Int. J. Sci. Technol. Res., libk. 8, zenb. 3, or. 132–140, 2019.
[13] P. Lumbanraja, «Pengaruh Karakteristik Individu , Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi ( Studi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara )», J. Apl. Manaj. |, libk. 7, zenb. 2, 2009, doi: 10.1177/009430610503400649.
[14] M. A. Wibowo eta Y. S. Putra, «Pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja serta Implikasinya terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Salatiga», Among Makarti, libk. 9, zenb. 17, or. 1–20, 2016.
458 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[15] A. Baihaqi, «Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Religiusitas
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Unza Vitalis Salatiga», Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah, libk. 6, zenb. 2, or. 43, 2015, doi: 10.18326/muqtasid.v6i2.43-64.
[16] H. H. Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia,. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
[17] M. Brury, «Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Sorong», J. Ris. Bisnis Dan Manaj., libk. 4, zenb. 1, or. 1–16, 2016.
[18] H. Purnomo eta M. Cholil, «Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Berdasarkan Motivasi Kerja Pada Karyawan Administratif di Universitas Sebelas Maret Surakarta», Manaj. Sumber Daya Mns., libk. Vol. 4, zenb. No. 1, or. 27–35, 2010.
[19] N. P. I. Ratnasari eta A. S. K. Dewi, «Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja Fisik Dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan», E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana, libk. 3, zenb. 7, or. 246091, 2014.
[20] R. L. Mathis eta J. H. Jackson, Human Resource Management (edisi. 10). Jakarta: Salemba Empat, 2011.
[21] Sunarso, «DAMPAK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA», J. Ekon. dan KewirausahaanJurnal Ekon. dan Kewirausahaan, libk. 9, zenb. 1, or. 75–85, 2002.
[22] L. Nirmalasari, «Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Kautsar Utama Bandung», Bandung, SMART – Study Manag. Res., libk. XI, No. 1, zenb. 2014, or. 14, 2014.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 459
Bab 29
Kepemimpinan dan Kenormalan Baru Pieter Sahertian33
Pengantar
Menghadapi perubahan yang seisemik (penuh jebakan) para pemimpin harus membuat pilihan-pilihan yang berani demi kelang-sungan dan eksistensi organisasinya. Harus diakui bahwa saat ini kita didorong keluar dari mindset dan model kerja yang telah mencapai titik jenuh tanpa kita sadari. Respons utama terhadap perubahan yang terjadi saat ini adalah upaya untuk membingkai kembali pemikiran kita bahwa perubahan yang mungkin belum saatnya terjadi, harus menjadi realitas kekinian secara tiba-tiba. Dalam setiap dinamika perubahan, selalu muncul sosok sebagai pribadi yang menggagas bahkan yang menjadi penggerak perubahan dalam sebuah organisasi. Sosok tersebut seringkali diberi predikat sebagai pemimpin. Dibalik keberhasilan yang diraih perusahaan-perusahaan besar, selalu memunculkan seseorang atau beberapa figure pemimpin yang tercatat namanya dalam sejarah perusahaan/organisasi tersebut.
Keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki seseorang yang diserahi tugas memimpin organisasi tersebut [1]. Organisasi pada dasarnya adalah sesosok makhluk hidup (a living organism). Ia dilahirkan, dewasa, tua, sakit dan dapat mati seperti layaknya makhluk hidup lainnya [2]. Pemimpinlah yang memiliki peran besar dalam tumbuh kembangnya sebuah organisasi. Tanpa pemimpin yang hebat perusahaan/organisasi akan mengalami proses alamiah seperti yang yang digambarkan diatas. “Tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa kepemimpinan dan pengorbanan” [3]. Para pemimpin perlu menyelaraskan pemikiran mereka dengan mengadopsi pendekatan kerja yang terdistribusi dan perlu bergerak melampaui kebijakan dan hasil untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat berhasil dengan baik.
Dalam situasi ketika terjadi perubahan yang mendadak seperti saat ini, maka untuk menggapai hasil maksimal dari semua upaya yang dilakukan di masa atau pasca pandemi, setiap pemimpin harus memerik-sa kapasitas yang ada padanya untuk siap menghadapi peru-bahan. Para
33 Dr. Pieter Sahertian, M.Si., Program Studi Magister Manajemen Universitas
Kanjuruhan Malang
460 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pemimpin harus mau bertanya pada dirinya sendiri, kepemimpinan yang bagaimana yang harus diterapkan pasca pandemi? Untuk bertahan hidup dan berkembang dalam normal baru, para pemimpin harus mau berubah. Pendekatan dan kemampuan konvensional, tidak mungkin efektif di lingkungan pasca-Covid-19. Bila kita masih memiliki pemahaman bahwa “pekerjaan” adalah apa yang dilakukan selama beberapa jam kemudian pulang, maka sikap seperti ini tidak memiliki tempat dalam normal baru, karena pada hakikatnya pekerjaan yang kita kerjakan sekarang adalah misi misi yang harus diwujudkan. Pekerja akan merasa bahwa pekerjaan mereka adalah misi jika pememipin mereka mempercayainya.
Diera pandemi dan setelahnya, adalah merupakan saat yang tepat bagi para pemimpin untuk berkomitmen mengembangan diri melalui pengembangan kesadaran diri yang tajam untuk membangun fondasi demi pertumbuhan. Seperti yang dikatakan Honore bahwa pemimpin yang baik disamping selalu belajar untuk melakukan hal-hal rutin dengan bak, pemimpin yang baik tidak takut untuk bertindak bahkan ketika dikritik. Pemimpin yang baik tidak takut untuk mengambil langkah-langkah yang tidak mungkin, karena tanda sejati seorang pemimpin yang hebat adalah bahwa orang-orang mengikuti dengan sukarela. Ketika organisasi menghadapi masa-masa sulit seperti yang terjadi saat ini, pemimpin harus selalu terlihat dan tampil untuk memberikan solusi bagi mitra kerjanya (bawahannya). Dalam situasi apapun seorang pemimpin harus tetap berada dalam optimisme dan antusiasme yang tinggi, karena sesulit apapun kondisinya pemimpin harus selalu tampil dan bertindak yang sering kali berbeda atau bertolak belakang dengan nuraninya atau dengan karakter aslinya.
Saat ini dunia berada dalam normal baru (new normal), yang dalam urusan apapun pasti ada gangguan dan perubahan karena fenomena ini mengharuskan kita untuk bertindak dan beradaptasi dan mengubah diri termasuk gaya kepemimpinan. Berbagai jenis bisnis mengalami fluktuatif. Tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan lama menjadi usang, karena telah terjadi perpaduan budaya baru yang telah menciptakan perspektif yang lebih beragam. Dimana-mana ada tuntutan baru untuk akuntabilitas dan transparansi. Untuk bertahan hidup dan menciptakan kesuksesan jangka panjang dalam iklim yang tidak terduga seperti itu, para pemimpin semua bidang usaha membutuhkan model dan kemampuan baru. Pemimpin tidak harus selalu berada di depan, tetapi selalu mencari tahu dimana mereka paling dibituhkan. Berada di
New Normal, Kajian Multidisiplin | 461
tempat yang tepat pada waktu yang tepat adalah tugas seorang pemimpin. Pemimpin harus bisa memahami tantangan sebenarnya dan bukan hanya tentang membuat orang melakukan apa yang ingin mereka lakukan, tetapi untuk membuat pengikut melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan.
Inilah kunci dari para pemimpin yang berhasil dalam lingkungan baru yang menuntut seberapa baik mereka mengidentifikasi, mengem-bangkan, dan memanfaatkan bakat-bakat terbaik. Bagaimana menginte-grasikan dan penyelaraskan strategi dan target kinerja organisasi serta bagaimana sikap dan perilaku pemimpin yang akan diterapkan dalam normal baru, merupakan inti dari kajian dalam tulisan ini.
Pembahasan
Cara Merespons Krisis Agar Menjadi Normal Baru
Dampak pandemi covid-19 telah mengubah cara hidup organisasi. Banyak organisasi telah memobilisasi rencana krisis mereka jika memilikinya. Dalam survey yang dilakukan oleh PwC’s Global Crisis Centre April 2020 terhadap pejabat keuangan global, sebagian besar responden mengatakan ketakutan terbesar mereka adalah akan terjadi-nya resesi global. Dalam situasi seperti ini, pemimpin harus membuat keputusan sulit. Tindakan yang akan mereka ambil harus taktis, tetapi harus selaras dengan tujuan organisasi. Kunci keberhasilan adalah persiapan, ketangkasan, data yang akurat dan kesediaan untuk menerima ide-ide briliant dari setiap lapisan organisasi. Dukungan berbagai komponen organisasi akan sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan di lingkungan yang baru ini. Apa yang dianggap sebagai suatu kegiatan Sumber daya Manusia seperti rasa memiliki, keterlibatan dan komitmen terhadap organisasi mengalami perubahan yang signifikan. Para eksekutif saat ini memiliki pegangan yang lebih kuat tentang bagaimana membangun dan mengembangkan potensi para karyawan mereka.
Dengan sumber daya manusia sebagai kendali utama, tanggung jawab untuk menggerakkan dan mengimplementasikan berbagai potensi dalam seluruh proses bisnis dapat berjalan sesuai rencana [4]. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa para pemimpin (CEO) terus memperjuang-kan agar pengembangan bakat dan kepemimpinan melalui peningkatan ketelitian melalui sebuah proses pengawasan akan dilakukan secara ketat. Hal ini sangat penting demi keberhasilan jangka panjang pada setiap organisasi.
462 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Organisasi yang sukses harus memberdayakan berbagai talenta
untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini. Implementasi manajemen talenta yang tepat akan sangat penting untuk membangun berbagai potensi dengan penilaian yang komprehensif. Seluruh pemimpin mulai dari level top manager sampai dengan lower manager perlu mengambil tanggung jawab pribadi untuk mewujudkan keberhasilan praktek manajemen bakat dalam setiap organisasi. Akan terjadi penyesalan dari para pemimpin yang tidak segera bertindak dan meninggalkan mitra kerja mereka, sehingga menyebabkan frustrasi dikalangan para karyawan. Oleh karena itu, pengembangan dan perencanaan suksesi sering tidak memadai. Rencana pengembangan para pemimpin senior (bukan hanya di tingkat menengah) harus dikaitkan dengan kebutuhan bisnis [5].
Salah satu kegagalan utama dari program pengembangan kepemimpinan adalah bahwa program-program tersebut tidak cukup diharapkan. Michelangelo mengatakan, “bahaya paling besar bagi kebanyakan dari kita bukanlah karena tujuan kita terlampau tinggi dan kita gagal mencapainya, tetapi karena tujuan kita terlampau rendah dan kita dapat mencapainya” [6]. Ketersediaan pemimpin dalam organisasi seringkali tidak sesuai dengan tuntutan. Hal ini terjadi bukan karena kurangnya program pengembangan yang terencana, namun karena adanya asumsi yang salah bahwa pemimpin senior tidak perlu pengembangan diri secara formal. Dengan konteks bisnis yang terus berubah, ketrampilan kepemimpinan harus terus disesuaikan untuk membantu mereka agar tetap relevan dan efektif. Para pemimpin perlu secara terus menerus mengubah diri mereka sendiri agar kemampuan untuk memimpin dalam situasi perubahan ini dapat berjalan dalam proses promosi yang normal.
Para pemimpin perubahan harus mau mengambil posisi pada berbagai level organisasi. Ada saat dimana mereka harus diatas, namun saat yang lain mereka harus melayani para pengikut mereka dengan mengilhami dan mendorong mereka untuk melayani orang lain. Para pemimpin tidak perlu menarik-narik pengikut yang enggan [7]. Sebaliknya, mereka harus membangkitkan semangat dengan antusiasme pengikut, mengilhami dengan pengabdian yang rendah hati serta mengajak berpikir dengan berbagi dan mendengarkan orang lain. Para pemimpin perubahan mau mengambil tanggung jawab untuk mendu-kung orang lain yang bekerja bersama mereka dan membantu mendapatkan sumber yang diperlukan pengikutnya untuk berkarya
New Normal, Kajian Multidisiplin | 463
dengan baik. Para pemimpin tidak henti-hentinya mengingatkan visi organisasi mereka untuk memastikan bahwa semua orang berada di jalur yang tepat.
Membalik Piramida Organisasi
Dengan memahami karakteristik kepmimpinan yang dibutuhkan di era baru ini (new normal era), kita dapat memastikan bahwa kepemimpinan semacam itu niscaya bertolak belakang dengan sebagian besar literatur kepemimpinan dan manajemen yang diakui dan populer serta masih berlaku sampai saat ini. Pada jaman dimana pemimpin bisnis yang sukses mempunyai simbol kekuasaan dan kesuksesan mereka sendiri, sikap dan pelayanan dari seorang pemimpin dianggap ketinggalan jaman, kuno, dan bahkan merendahkan martabat. Kebanyakan manajer perusahaan, masih berpikir dengan paradigma lama dimana otoritas dan struktur kekuasaan dibangun seperti sebuah piramida [8]. Pada umumnya, organisasi menggunakan model piramida seperti diagram berikut ini:
Model Komando dan kontrol Kepemimpinan
Pelanggan
Model Komando dan Kontrol ini bersifat hierarkis, formal dan
komunikasinya bersifat satu arah atas---bawah. Kebijakan dan keputusan yang dibuat di atas dan dikomunikasikan ke bawah kepada anggota staf yang statusnya lebih rendah, yang memiliki akses kepada para pelanggan. Pola komunikasi semacam itu biasanya cenderung berjalan lambat dan seringkali mematahkan inisiatif atau kurang dinamis. Dalam struktur atas—bawah, perhatian staf terpaku pada apa yang dikehendaki oleh manajer langsung mereka. Para pekerja yang berada di garda
Manajemen Senior
Manajemen Level Menengah
Petugas Garda Depan
Komunikasi Atas Bawah
464 | New Normal, Kajian Multidisiplin
terdepan ini lebih memperhatikan bagaimana memuaskan bos langsung daripada memenuhi harapan dan kebutuhan nyata pelanggan.
Lebih lanjut D’Souza mengatakan bahwa, dalam revolusi pelayanan di dunia industri yang menuntut dunia bisnis lebih berorientasi pada pelanggan, maka struktur organisasi tradisional perlu ditinjau ulang. Jika orientasi pada memposisikan pelanggan adalah “raja”, maka piramida tersebut harus dibalik seperti gambar berikut:
Model Pelayan dan Dukungan Pelanggan
Kebanyakan dari kita terlanjur terbiasa melihat piramida organisasi secara tradisional sehingga jajaran kepemimpinan dan manajemen dipandang berada “di atas” staf. Bahkan para staf memposisikan diri mereka bekerja “di bawah” bos mereka. Anggapan bahwa seorang pemimpin atau manajer seharusnya berada pada posisi di “di atas” staf, merupakan persepsi yang merendahkan peran, kecerdasan, kompetensi dan kemampuan mereka. Membalik piramida organisasi yang memusatkan perhatian pada staf, menempatkan mereka langsung bersentuhan dengan pelanggan. Dalam piramida terbalik tersebut, kepemimpinan dan manajemen memberikan pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para staf untuk menjalankan apa yang menjadi fungsi utama organisasi manapun. Dari sisi pelanggan, petugas garda terdepan ini merupakan orang-orang yang menentukan citra organisasi yang dirasakan oleh pelanggan. Dengan model piramida seperti itu, seluruh staf fungsional dan manajemen benar-benar hadir untuk
Petugas Garda Depan
Manajemen Berfungsi Sebagai Pendukung
Kepemimpinan
Memberikan Visi
Komunikasi Dua Arah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 465
mempermudah para petugas garda terdepan dalam memuaskan dan memenuhi kebutuhan nyata para pelanggan.
Kepemimpinan yang relevan dengan piramida kedua, adalah kepemimpinan bertipe pelayan [9]. Adapun ciri-ciri adalah: 1. Mendengarkan: pada umumnya seorang pemimpin dihargai karena
kemampuannya dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Kemampuan ini perlu diperkuat dengan komitmen yang mendalam untuk mendenganrkan orang lain secara sungguh-sungguh. Para pemimpin dengan tipe ini berusaha untuk mengidentifikasi kemauan mitra dan tim kerjanya. Mendengarkan bertujuan untuk memahami apa yang dikatakan (dan yang tidak dikatakan). Kemauan untuk mendengarkan akan memperdalam tingkat komunikasi dan pemahaman [10]. Seorang pemimpinan yang mau mendengarkan, menguatkan orang lain dan membantu mereka untuk memperjelas siapa diri mereka dan bagaimana mereka dapat bertumbuh.
2. Empati: para pemimpin pelayan berusaha berempati pada orang lain, mengenali keistimewaan dan talenta mereka yang unik. Mereka mengandaikan niat baik rekan kerjanya dan tidak menolak mitranya, bahkan ketika orang lain tidak dapat menerima perilaku atau kinerja mereka sekalipun. Pemimpin pelayan yang paling sukses menjadi pendengar empatik yang terlatih.
3. Menyembuhkan: belajar menyembuhkan merupakan kekuatan yang dasyat untuk melakukan transformasi dan integrasi. Salah satu kekuatan para pemimpin pelayan adalah kemampuan mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Dalam The Servant as Leaders, dijelaskan bahwa: “ada sesuatu yang secara halus dikomunikasikan dengan orang yang dilayani dan dipimpin sehingga terjadi kontak antara pemimpin dengan yang dipimpin” [11].
4. Persuasi: para pemimpin pelayan mengandalkan persuasi daripada otoritas jabatan mereka dalam mengambil keputusan. Mereka berusaha meyakinkan orang lain dan bukan memaksakan penyesuaian. Pemimpin pelayan, efektif dalam membangun konsensus dalam kelompok. Persuasi bertujuan untuk membangun kepercayaan orang yang dipimpin. Agar pemimpin layak dipercaya maka mereka harus memiliki karakter sebagai seorang pribadi dan kecakapan yang dapat dilakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa seseorang yang memperoleh angka rendah untuk karakter, mutlak tidak mempunyai kesempatan untuk
466 | New Normal, Kajian Multidisiplin
terlihat sebagai sebagai seorang pemimpin besar khususnya dalam jangka panjang [6]. Para pemimpin yang kurang memiliki karakter, harus berjaga-jaga jangan sampai orang lain mengetahui kebenaran tentang diri mereka.
5. Komitmen pada pertumbuhan semua orang: para pemimpin pelayan percaya bahwa semua orang mempunyai nilai dasar yang melampaui kontribusi nyata mereka sebagai pekerja. Oleh karenanya, mereka mempunyai komitmen yang mendalam pada pertumbuhan semua individu.
Kepemimpina dalam Realitas Baru (Normal Baru) Menghadapi dinamika sebagai akibat pandemi seperti yang
dialami saat ini, setiap orang pasti memiliki keinginan sekaligus berharap-harap cemas agar kondisi dapat normal kembali seperti sebelum terjadinya pandemi. Ketika organisasi di berbagai belahan dunia sibuk memikirkan bagaimana memulai aktivitas dengan situasi yang sangat terbatas (untuk kasus Indonesia kita kenal dengan istilah PSBB dan berbagai terminologi lainnya), para pemimpin perlu beralih dari respons krisis ke pemikiran tentang bagaimana peran organisasi dan kepemimpinan dalam jangka panjang. Bagi para pemimpin, tantangan untuk membimbing orang/karyawan dalam suasana ketidakpastian ke dalam normal baru, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam situasi krisis seperti saat ini, sikap empati dan fleksibilitas merupakan kualitas kepemimpinan yang penting untuk dikedepankan. Ketika karyawan mengalami perubahan budaya kerja yang mendadak dan radikal seperti kebutuhan untuk bekerja dari jarak jauh atau bekerja di ruang kerja yang sangat terbatas dalam jangka waktu yang lama, kualitas relasi antar pemimpin dan karyawan sangat dibutuhkan untuk menjaga agar tim tetap kompak, keterlibatan secara penuh dan termotivasi tetap terjaga.
Dalam menghadapi keadaan yang tak terduga (seperti pandemi) saat ini, organisasi akan sangat bergantung pada pemimpin yang memiliki empati. Setiap krisis memiliki sisi yang mnakutkan dan tragis, namun krisis juga menawarkan pelajaran yang berharga. Bahkan ada pandangan yang berkembang dalam masyarakat yang mengatakan bahwa pandemi covid-19 disamping menimbulkan krisis dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikann dan moral. Namun pada bagian lain pandemi ini juga mendatangkan “berkah” berupa terjadinya akselerasi dalam bidang kesehatan dan pelayan publik, penyadaran masalah hidup sehat dan menjaga lingkungan serta perubahan mindset
New Normal, Kajian Multidisiplin | 467
di segala bidang kehidupan. Apa yang kita pelajari hari ini tentang cara-cara bekerja, akan sangat berharga untuk waktu-waktu mendatang dan keberlanjutannya sangat bergantung pada para pemimpin. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin, akan menentukan kemampuan daya tahan organisasi yang dipimpinnya dalam menghadapi krisis yang lebih kuat dari sebelumnya.
Untuk mengasah empati dan kemampuan pemimpin dalam beradaptasi dengan situasi krisis, mereka membutuhkan tiga elemen kepemimpinan, yaitu kepala (head), hati (heart) dan tangan (hands), [12].
Memimpin dengan kepala menuntut tanggung jawab dari pimpinan untuk membuat visi masa depan yang jelas dan untuk menetapkan arah yang jelas menuju kesuksesan yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak organisasi yang berhasil dan unggul, karena mereka mampu menciptakan visi aspirasional yang memandu berbagai hal dalam organisasi, mulai dari strategi yang menyeluruh hingga tindakan dan motivasi karyawan secara individu. Palajaran yang dipetik dari pola ini adalah, dengan visi yang kuat akan membantu seluruh anggota organisasi berkembang dalam pekerjaan mereka. Agar tetap relevan dalam lingkungan yang berubah, visi harus sering ditinjau kembali dan dijaga dengan cermat. Pemimpin yang memberdayakan memimpikan masa depan ideal yang memberi arah pada organisasi mereka. Mereka mengartikulasikan dan mendapatkan dukungan untuk mencapai visi-visinya hingga menyatu ke dalam organisasi. Memimpin dengan kepala mengharuskan pemimpin untuk membayangkan masa depan dan prioritas yang dibutuhkan untuk berhasil.
Kepemimpinan dengan “hati” bertujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan karyawan. Sebelum pandemi sebagai akibat dari covid-19, hati adalah salah satu unsur kepemimpinan yang paling diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa hanya ada satu dari empat pemimpin yang memiliki keterampilan empati yang tinggi. Sebuah studi yang dilakukan di University of Michigan menunjukkan, terjadi penurunan 34% hingga 48% dalam keterampilan yang terkait dengan empati selama periode delapan tahun terakhir [12]. Ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan, mengingat empati membantu membangun hubungan yang kuat antara pekerja lokal dan pekerja jarak jauh sambil memotivasi tim dan mendorong kinerja. Sekaranglah saatnya bagi perusahaan untuk menciptakan budaya yang lebih empati. Tentu saja, suatu budaya hanya dapat dipercaya jika memenuhi janjinya melalui saat-saat baik dan buruk.
468 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Penerapan kepemimpinan dengan “tangan” dimaksudkan agar
kemampuan inovatif dan tangkas yang dimiliki seorang pemimpin dapat dipergunakan untuk ketepatan mengeksekusi. Tujuan yang ditetapkan organisasi dapat berfungsi sebagai bintang penuntun untuk mewujudkan keberhasilan. Namun kemampuan menavigasi organisasi dalam aktivitas keseharian, berada dalam kendali pemimpin yang mampu membangun komunikaasi dua arah yang harmonis, sangat diperlukan. Model kepemimpinan perintah dan kontrol seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara implisit bertumpu pada komunikasi satu arah. Pola relasi ini telah berjalan dengan cukup baik di lingkungan yang stabil. Namun dengan meningkatnya kompleksitas urusan yang harus dikerjakan oleh organisasi apalagi dengan peningkatan yang eksponensial dalam beberapa tahun terakhir ini, komunikasi satu arah (atas—bawah) sangat tidak efektif.
Para pemimpin perlu mengerahkan kemampuan ekstra,
khususnya mereka yang mengendalikan organisasi bisnis global (multi nasional). Mereka telah memahami bagaimana tantangan untuk menyatukan tim/karyawan yang bekerja di lokasi yang berbeda. Namun teknologi telah mempertemukan mereka dalam komunikasi virtual untuk saling berbagi dan mensolusikan permasalahan maupun menerima kebijakan yang harus mereka kerjakan bersama. Di ruang digital inilah, semua anggota tim dari seluruh penjuru dunia dapat bertemu, mencari informasi baru, dan berbagi pertanyaan dan ide. Ruang informal ini telah membangun rasa memiliki dan keterlibatan, dan pada gilirannya menciptakan global team yang benar-benar kolaboratif. Banyak perusahaan yang sebelumnya tidak menemukan solusi yang baik untuk menghadapi tantangan tenaga kerja yang tersebar, namun sekarang mereka telah memiliki cara yang jauh lebih baik untuk melakukan-nya. Tantangan bagi para pemimpin di masa kini adalah memberi arahan, memberikan otonomi, dan fokus pada hasil daripada kegiatan, terutama ketika pekerjaan terus menjadi lebih fleksibel dan didistribusikan.
Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya menggabungkan visi dengan keterampilan kepemimpinan praktis yang kuat dan empati yang mendalam. Dengan kata lain apa kelebihannya ketika seorang pemimpin harus mengimplementasikan kepemimpinan dengan “kepala, hati dan tangan”. Mungkin tampak sulit untuk diukur, dan upaya yang diperlukan untuk pembenaran terhadap pola kepemimpinan tersebut
New Normal, Kajian Multidisiplin | 469
dan sulit untuk dijustifikasi. Di berbagai organisasi yang menyatukan kepala, hati, dan tangan dalam pola kepemimpinannya, melihat keuntungan yang walaupun tidak secara kuantitatif, namun di masa yang penuh gejolak sebagai dampak dari pandemi ini, kepemimpinan dengan kepala, hati, dan tangan dapat menjadi rujukan dalam membangun keunggulan kompetitif mereka untuk masa depan.
Krisis seperti yang dihadapi berbagai organisasi saat ini, memaksa manajemen dan pemimpin untuk berani melakukan perubahan dan mampu beradaptasi dengan kecepatan luar biasa.
Langkah Konkrit Apa yang Perku Disiapkan Pemimpin
Tidak ada yang tahu, apa yang diharapkan saat kita keluar dari krisis akibat pandemi. Namun lingkungan kerja tidak mungkin kembali ke situasi “normal” yang akan dihadapi ke depan. Oleh karena itu, kesiapan menerima perubahan itulah yang harus dimiliki setiap pemimpin. Pendekatan dan cara-cara konvensional tidak mungkin efektif dipaksakan untuk diterapkan dalam lingkungan pasca krisis. Dalam tulisannya yang berjudul “Leadership For The New Normal: Are You Ready?” Perkins menawarkan langkah-langkah untuk penilaian dan pertumbuhan [13].
Langkah 1: Periksa Asumsi Anda
Umumnya para pemimpin sering berpikir dan bertindak berdasarkan auto pilot. Kita cenderung mengulangi tindakan yang menghasilkan kesuksesan di masa lalu. Pendekatan ini mungkin relevan ketika organisasi kita berada dalam keadaan stabil. Namun kita tahu bersama bahwa hampir tidak ada yang tidak berubah bahkan segala sesuatu cepat berlalu. Hampir setiap terobosan penting merupakan hasil perubahan yang berani dari cara-cara berpikir tradisional [14]. Dalam lingkungan ilmiah, perubahan dramatik, revolusi pemikiran, lompatan-lompatan besar pengetahuan, dan pembebasan seketika dari batasan-batasan lama disebut “perubahan paradigma”. Perubahan paradigma ini menawarkan cara-cara berpikir yang sama sekali baru mengenai masalah-masalah lama. Asumsi usang mungkin akan mengecewakan, karena itu tuliskan asumsi anda tentang tantangan kepemimpinan yang akan dihadapi. Identifikasi asumsi-asumsi yang ada dan tanyakan pada diri sendiri, “Apa yang akan terjadi (mungkinkah terjadi perbedaan) jika asumsi-asumsi tidak ada? Apakah harus membuat keputusan yang berbeda?”. Ajaklah mitra kerja atau karyawan anda untuk adu argu-ment-tasi dan brainstorming dengan ide-ide yang menantang. Bila perlu
470 | New Normal, Kajian Multidisiplin
minta mereka untuk menunjukkan apa yang terlewatkan dan tidak anda lakukan sebelumnya. Melakukan percakapan dan diskusi dengan orang lain, dapat membawa perspektif baru. Tantangan baru mengharuskan seorang pemimpin membingkai dan memperseprsi masalah mereka secara berbeda. Buang segala kecenderungan untuk menegaskan otoritas atau superioritas dan sebagai gantinya, libatkan diri secara aktif dalam setiap diskusi dan percakapan bersama-sama.
Langkah 2: Berkomitmen pada Pembelajaran yang Bersengaja
Para pemimpin konvensional sering berasumsi bahwa keahlian mereka akan memungkinkan mereka untuk mengatasi persoalan kepemimpinan yang dihadapi. Namun, kompleksitas dunia saat ini membuktikan bahwa keunggulan pengetahuan setiap individu sangatlah terbatas. Walaupun keahlian yang dimiliki seorang pemimpin dapat membantunya untuk maju dengan sukses, namun kemampuan tersebut seringkali membatasi dan mengendalikannya tentang cara berpikir bagaimana memanfaatkan peluang yang ada dan bagaimana mengha-dapi tantangan di depan mata. Oleh sebab itu setiap pemimpin harus mampu mengenali nilai dan kekurangan wawasan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membatasi kedalaman dan luasnya strategi untuk mencapai tujuan. Belajar bagi seorang pemimpin merupakan suatu kebutuhan utama, dan merupakan proses yang terus-menerus berlang-sung dalam segala bentuknya. Dalam buku yang berjudul “Menjadi Manusia Pembelajar” dijelaskan bahwa tugas pertama manusia dalam proses menjadi dirinya yang sebenarnya adalah menerima tanggung jawab untuk menjadi pembelajar [15]. Salah satu cara untuk belajar adalah mempelajari pengalaman sendiri yang baru dan unik.
Langkah 3: Tunjukkan Tujuan Anda
Idealnya, semua organisasi memiliki tujuan sebagai pemandu mewujudkan cita-citanya. Para manejer strategis mengakui bahwa untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, perencanaan strategis dalam setiap organisasi harus menetapkan tujuan. Terdapat tujuh kriteria yang sebaiknya digunakan dakam mempersiapkan tujuan jangka panjang, yaitu fleksibel, terukur, memotivasi, sesuai, dapat dipahami, dan dapat dicapai [16]. Suatu tujuan dikatakan fleksibel apabila tujuan tersebut dapat disesuaikan terhadap perubahan yang sebelumnya tidak diketahui atau yang sifatnya luar biasa dan dapat dijadikan acuan untuk berada dalam suasana kompetitif. Tujuan yang terukur adalah tujuan yang jelas dan konkret, menyatakan apa yang akan dicapai dan kapan hal itu akan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 471
dicapai. Tujuan yang memotivasi menjadi dasar setiap orang yang bekerja untuk produktif jika tujuan tersebut berada pada tingkat yang memotivasi, yaitu tingkat yang cukup tinggi sehingga menantang, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga membuat frustrasi, atau terlalu rendah sehingga mudah dicapai. Tujuan juga harus dapat dicapai agar bukan hanya mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Banyak kasus yang terjadi pada organisasi bisnis yang mengalami kerugian karena penetapan tujuan yang sulit untuk diimplementasikan khususnya yang terkait bidang-bidang utama yang menentukan produktifitas mereka, seperti proyeksi penjualan, pemasaran, kualitas produksi dan lain-lain. Tujuan juga harus sesuai dengan sasaran yang luas dari perusahaan/organisasi. Tujuan harus merupakan satu langkah menuju pencapaian sasaran secara keseluruhan, bahkan tujuan yang tidak konsisten dengan misi perusahaan dapat menghalangi terwujudnya sasaran perusahaan. Akhirnya tujuan harus dapat dipahami oleh semua tingkatan/level organisasi agar tujuan tersebut dapat dicapai. Mereka harus memahami kriteria-kriteria utama sehingga tujuan harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh si pelaksana sebagaimana si pembuat tujuan memahaminya.
Penutup
1. Dunia kita selalu berubah, namun krisis akibat pandemi telah meningkatkan perubahan yang sedang berlangsung dan menciptakan beberapa perubahan baru. Untuk memimpin dengan sukses dalam pemandangan yang berkembang saat ini, para pemimpin harus tumbuh dan mau berubah juga. Sekarang adalah waktunya untuk mempersiapkan masa depan yang baru.
2. Para pemimpin perlu mengenali dengan saksama setiap pekerjaan yang dihadapi daripada membiarkan dirinya larut dalam nostalgia ke masa lalu sebelum terjadi krisis sebagai dampak dari pandemi covid-19. Dalam menghadapi ketidak pastian yang sedang berlangsung, para pemimpin memiliki salah satu atau dua opsi, bersembunyi dan mengurungkan diri sambil menunggu badai akan berlalu atau secara proaktif memikirkan cara mengarahkan organisasi mereka untuk menavigasi periode turbulensi yang dihadapi sambil menjaga kekompakan tim kerja yang ada.
3. Dalam menghadapi situasi krisis, hadirnya manajemen krisis sangat diperlukan untuk diperangi ketika masalah baru muncul. Memiliki tim manajemen krisis yang berdedikasi akan sangat membantu para pemimpin tertinggi untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting
472 | New Normal, Kajian Multidisiplin
untuk disolusikan. Itulah sebabnya penting untuk mendirikan pusat komando krisis untuk mengelola tantangan dengan melibatkan seluruh anggota tim, mulai dari pimpinan eksekutif sampai level yang terbawah untuk turun.
Rujukan
[1]. S.P. Siagian, Manajemen Sumberdaya Manusia, Cetake-24, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
[2]. R. Kasali, Change, Jakarta: Penerbit Gramedia. 2007. [3]. R. L. Honore,. Leadership in The New Normal. Lafayette,
Lousiana: Acadian House Publishing. 2012 [4]. R. Patten and Hugh Arnold,. Welcome to the new normal. What
does it mean for leaders? https://www.rotman.utoronto.ca/Professional Development/Executive-Programs/FeaturedArticles/NewNormal,2020
[5]. C.D. McCauley & E. Van Velsor,. Hand Book of Leadership Development, San Francisco: Center for Creative Leadership. 2004
[6]. J.H. Zenger & J. Folkman,. The Handbook for Leaders (Alih Bahasa: Paul Alfried Rajoe), Jakarta: Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer2004.
[7]. J.W. Wafford. Transforming Christian Leadership, Grand Rapids, Michigan: Baker Book.
[8]. A. D’Souza,. Proactive Visionary Leadership (Ed. Lilis Setyayanti), Jakarta: Trisewu Nagawarsa. 2007
[9]. L. Spears,. Insights on Leadership in Action Excursion into Sociology of Action, Washington D.C.: The Falmer Press. 1993
[10]. R. Greenleaf,. Servant Leadership: A Journey into the Nature of
Legitimate Power and Greatness, New York: Paulist Press. 1977 [11]. R. Greenleaf,. The Power of Servant Leadership, San Fransisco:
Berret-Koehler. 1998 [12]. R. Strack, J. Kugel, S. Dyrchs, and M. Tauber,. Leadership in the
New Now, https: //www.bcg.com/publications/2020/leadership-post-covid-19.aspx2020
[13]. K.M. PERKINS,. LEADERSHIP FOR THE NEW NORMAL: ARE YOU
READY?
HTTPS://WWW.FORBES.COM/SITES/KATHYMILLERPERKINS/2020/0
New Normal, Kajian Multidisiplin | 473
5/18/LEADERSHIP-FOR-THE-NEW-NORMAL-ARE-YOU-READY/#41F650568213,2020
[14]. S. Covey,. Kepemimpinan yang Berprinsip (Alihbahasa: Julius Sanjaya), Jakarta: Binarupa Aksara. 1997
[15]. A. Harefa,. Menjadi Manusia Pembelajar, Jakarta: Penerbit Kompas,2000.
[16]. J.A. Pearce II & R.B. Robinson, Jr. Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, (Penerjamah: Nia Pramita Sari), Jakarta: Penerbit Salemba Empat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 475
Bab 30
Wacana Pagebluk Covid-19 pada Masyarakat Jawa: Kajian Register Prembayun Miji Lestari, Retno Purnama Irawati, Agus Yuwono34
Pengantar
Wabah Covid-19 ditetapkan WHO sebagai pandemi global yang melanda Indonesia dan banyak negara di dunia, menjadi wacana realita yang telah mengubah tatanan di banyak sendi kehidupan. Indonesia sejak 14 Maret 2020 melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) juga menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Akibat adanya Covid-19 ini tentu menjadi masalah yang sangat penting untuk dikaji dengan berbagai pendekatan, termasuk dengan pendekatan bahasa. Lahirnya ekspresi-ekspresi berbahasa sebagai implikasi dari adanya Covid-19, menjadi kajian linguistik yang penting untuk diteliti secara mendalam. Masyarakat Jawa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tentu memiliki wacana sesuai dengan bahasa dan budayanya mengenai Covid-19.
Masyarakat Jawa dalam menghadapi adanya Covid-19, tidak bisa terlepas dari adanya sistem pengetahuan (cognition system) lokal yang menyangkut pola pikir, pandangan hidup (way of life) dan pandangan terhadap dunianya (world view). Manusia Jawa memiliki terminologi sendiri dalam menyebut berbagai penyakit massal yang melandanya, yakni “pageblug”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pagebluk diartikan sebagai wabah penyakit atau epidemi. Apapun jenis virus itu, asalkan berpotensi menjangkiti orang dengan jumlah banyak, maka disebut pagebluk [1].
Adanya Covid-19, menimbulkan banyak reaksi dan persepsi dari masyarakat Jawa. Reaksi khawatir, takut, sedih, bingung, menganggap Covid-19 adalah bagian dari pagebluk atau karma, serta reaksi berbeda lain yang pada dasarnya secara substansial adalah sama yakni merasa risau dengan adanya masalah tersebut. Risau menurut KBBI merupakan: 1) perasaan gelisah; rusuh hati: hatinya merasa-bercampur cemas; 2) rusuh (kacau, tidak aman): selama keadaan masih (dalam konteks ini keadaan adanya Covid-19). Kerisauan akan imbas dari adanya Covid-19, misalnya
34 Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum., Retno Purnama Irawati, S.S., M.A, Drs. Agus
Yuwono, M.Pd., M.Si., Dosen pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Semarang
476 | New Normal, Kajian Multidisiplin
banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK, bahan kebutuhan sembako minim atau langka keberadaannya, antara satu orang dengan lainnya jadi berjarak karena adanya social distancing, bergesernya budaya salaman karena ada anjuran untuk tidak bersalaman agar tidak saling tertular virus, cemas jika ada kerumunan orang, takut mau keluar rumah, khawatir dengan perekonomiannya, merupakan bentuk kerisauan.
Selain berpotensi menjadi bencana, adanya pagebluk Covid-19 juga memunculkan sisi kreatif bagi masyarakat Jawa untuk melahirkan berbagai kreativitas dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk memunculkan istilah-istilah khas berbasis bahasa-budaya Jawa terkait Covid-19. Wacana pagebluk Covid-19 pada masyarakat Jawa yang menjadi fokus kajian ini yakni bentuk-bentuk register berbahasa Jawa yang berkaitan dengan pembicaraan Covid-19 dan aplikasi penggunaannya. Terdapat beberapa penelitian linguistik mengenai register dan Covid-19.
Penelitian yang dilakukan oleh Junieles [2] mengkaji register kesehatan di era pandemi covid-19 yang muncul di berbagai media online. Temuan penelitian berupa bentuk register yang terklasifikasi menjadi tiga yakni lingual, selingkung terbatas, dan terbuka. Temuan lain berupa fungsi register yang terbagi empat yaitu fungsi instrumental, regulasitoris, representasional, dan heuristik. Nurdiyani [3] meneliti sikap bahasa gubernur Jawa Tengah: Ganjar Pranowo terhadap maklumat gotong royong dalam menghadapi virus corona. Kajian dalam bidang Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) berdasar perspektif appraisal.
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hampir semua ranah appraisal digunakan oleh Gubernur Jawa Tengah pada maklumat gotong royong dalam mengatasi virus corona di wilayah yang dipimpinnya. Sumber sikap yang dipakai yakni monoglos dan heteroglos. Persamaan penelitian Junieles [2], Nurdiyani [3] dan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai register atau virus corona. Perbedaannya dalam penelitian ini berfokus register terkait covid-19 yang digunakan masyarakat Jawa, sementara penelitian terdahulu berfokus pada register kesehatan dan sikap bahasa terhadap maklumat gotong royong untuk mengatasi adanya virus corona. Perbedaan lain terletak pada subjek penelitian, fokus permasalahan yang dirumuskan, unit analisis yang diteliti, dan hasil penelitian yang ditemukan. Apa yang dibahas dan ditemukan pada penelitian sebelumnya, dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis data yang didapatkan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 477
Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya mengenai register, bahasa Jawa, budaya Jawa dan kearifan lokalnya. Register merupakan variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Ada beberapa ahli bahasa yang memberikan pengertian konsep register, yakni: Wardhaugh, Hudson, Spolsky, Chaer, dan Holmes. Wardaugh [4] mendefinisikan: registers are sets of vocabulary items associated with discrete occupational or social groups. Register as varieties according to user ‘register adalah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya’.
Sejalan dengan Hudson [5], Spolsky [6] menyebut register is variety associated with a specific function ’register adalah variasi bahasa yang dihubungkan dengan fungsi khusus’. Pendapat berikutnya menyebut register sebagai variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk bidang tertentu, semisal jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi ini dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bidang ini menyangkut kegunaan bahasa untuk keperluan apa atau dalam bidang apa. Setiap bidang biasanya memiliki sejumlah kosakata khusus yang tidak digunakan dalam bidang lain [7]. Register yakni variasi bahasa yang terkait dengan parameter situasional seperti: penerimanya, latar atau setting, model komunikasi, dan topik [8]. Lestari [9][10] menyebut adanya register karena dua hal: (1) muncul karena kesibukan bersama yang tidak berkaitan dengan profesi, dan (2) muncul karena aktivitas dan profesi sosial yang sama. Dalam hal ini, pembicaraan mengenai Covid-19 termasuk dalam register yang timbul karena adanya kesibukan yang tidak berhubungan dengan profesi. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi masyarakat Jawa mengenai Covid-19 di lingkungan sosial kelompok yang diteliti. Kesimpulannya. register menunjukkan bahasa yang khas atau khusus dalam pemakaiannya.
Berikutnya, ulasan mengenai bahasa Jawa, budaya dan kearifan lokal Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu masyarakat Jawa yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Bahasa ini termasuk anggota rumpun bahasa Austronesia yang memiliki tata kalimat yang mirip dengan bahasa Indonesia dan dalam kosakatanya pun terdapat banyak kata seasal (cognate) dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia [11]. Selanjutnya, ulasan mengenai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat di negara manapun memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Budaya dan tradisi tersebut memiliki makna dan nilai penting diantaranya sebagai acuan bagi
478 | New Normal, Kajian Multidisiplin
masyarakatnya dalam menjalani kehidupan, termasuk menghadapi perbedaan-perbedaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Tradisi-tradisi itulah yang disebut dengan kearifan lokal atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat [12]. Dalam konteks ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Jawa.
Ahimsa [13] mendefinisikan kearifan lokal sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar. Istilah lain dari kearifan lokal yakni local genius pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales (1948-1949), dan local wisdom yang merupakan kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan [14]. Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak berupa: nasihat, pepatah, pantun, syair, folklor (cerita lisan); aturan, prinsip, norma, dan tata aturan sosial yang menjadi sistem sosial; seremonial dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial [15]. Kearifan lokal Jawa merupakan bentuk kecerdasan lokal masyarakat etnik Jawa untuk mengatasi persoalan hidup utamanya terkait dengan interaksi sosial. Adanya perbedaan agama, latar belakang dan status sosial berpotensi memunculkan konflik antar individu dalam masyarakat. Hal inilah yang mendorong masyarakat Jawa untuk menjaga nilai tradisi-tradisi lokal yang dirasa mampu menyelesaikan atau meredam munculnya konflik.
Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia terkait dengan pembicaraan seputar Covid-19. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: 1) peristiwa tutur lisan dan tulisan pada masyarakat Jawa mengenai pembicaraan Covid 19. Analisis data yang dipergunakan berupa tiga proses yang saling berhubungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.
Pembahasan
Untuk mengetahui wacana pagebluk Covid-19 masyarakat Jawa tentang adanya Covid-19, dilakukan penelitian baik yang bersumber dari tuturan maupun hasil wawancara dengan masyarakat Jawa yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk register yang berkaitan dengan seputar Covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dan berbasis budaya Jawa, serta belum banyak diteliti. Hal ini mendasari penulis untuk meneliti register Covid-19 yang menunjukkan identitas
New Normal, Kajian Multidisiplin | 479
kultural etnik Jawa di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini juga mengungkap hubungan kata-kata spesifik yang termasuk dalam register Covid-19 berbahasa dan berbasis budaya Jawa dalam aplikasi kehidupan masyarakat Jawa. Berikut bentuk-bentuk register berkaitan dengan pembicaraan covid-19 yang ditemukan pada masyarakat Jawa yang diteliti. Tabel 1. Register Pembicaraan Seputar Covid-19 oleh Masyarakat Jawa
Istilah Covid-19
Maksud dan Maknanya Register-Register Berkaitan
Covid-19 oleh Masyarakat Jawa
Corona Virus yang menyebabkan beberapa masalah pernafasan akut parah
Corona oleh masyarakat Jawa diplesetkan menjadi Korona yang merupakan akronim dari Kondisi ora ono dana yang artinya ‘kondisi tidak mempunyai dana’. Register dalam bentuk plesetan tersebut muncul lantaran dengan adanya pandemi corona, menyebabkan perubahan pada sisi ekonomi, karena terbatasnya pemasukan atau terimbas adanya PHK.
Covid COVID singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), dan Disease (D, penyakit), yang bermakna sebuah infeksi penyakit yang bisa bisa menular, disebabkan oleh virus corona (bisa menyebabkan berbagai macam penyakit)
Covid dalam masyarakat Jawa diplesetkan menjadi saka nge-vit ‘dari bersepeda’. Aktivitas bersepeda atau gowes menjadi salah satu pilihan aktivitas masyarakat selama menghadapi pandemi Covid-19.
Isolasi Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), isolasi adalah pemisahan suatu hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lainnya. Jadi maksud isolasi merupakan upaya untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 dengan cara memisahkan orang yang terkena dan tidak terkena covid-19
Kata ndelik ‘bersembunyi’, tapa ‘bertapa’ digunakan oleh masyarakat Jawa untuk mengganti istilah isolasi pada saat membicarakan masalah terkait seputar virus corona/covid-19 Selain itu, untuk memperjelas istilah isolasi, dipergunakan kalimat sing loro diobatke dikurung ben ra nulari wong liyo (isolasi untuk orang sakit, diobati, lalu menyendiri agar tidak menulari orang lain)
karantina Menurut KBBI, karantina berarti tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna
Jika mengacu pada lokasi, ditemukan adanya istilah panggonan wingit ‘tempat angker’ yang digunakan oleh masyakat
480 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Istilah
Covid-19 Maksud dan Maknanya
Register-Register Berkaitan Covid-19 oleh Masyarakat Jawa
mencegah terjadinya penularan penyakit dan sebagainya. Bagi orang yang dikarantina yang diduga terpapar Covid-19 tanpa adanya gejala, dihimbau untuk tetap berdiam di tempat penampungan (baik rumah maupun rumah sakit) serta tidak keluyuran kemana-mana hingga hasil tes Covid-19 menunjukkan hasil negatif
Jawa untuk memadankan istilah karantina. Masyarakat Jawa menyebut istilah karantina menjadi karantina nggo sing sehat kui artine wis pokoke anteng ning omah wae ora usah kluyuran Bagi orang yang dikarantina atau dipingit ‘tidak boleh pergi-pergi keluar rumah’ karena diduga terpapar virus corona, maka dihimbau untuk berdiam di panggonan wingit yang telah disediakan oleh pihak terkait yang menangani adanya kasus ini.
Negatif Terbebasnya sesorang dari adanya virus corona/covid-19
Nol, kosong, bebas virus ‘terbebas dari virus’, register ini digunakan oleh masyarakat Jawa pada saat membicarakan tentang pagebluk covid-19, ini untuk menggantikan istilah negatif
ODP ODP singkatan dari Orang Dalam Pemantauan. Makna dari ODP yakni seseorang yang mengalami salah satu gejala dari infeksi virus Corona/Covid-19
Dalam masyarakat Jawa istilah ODP diplesetkan menjadi Ora Duwe Penghasilan ‘Tidak Mempunyai Penghasilan’ sebagai akibat dari adanya pandemi pagebluk Covid-19. Untuk menjelaskan makna ODP, dipergunakan kalimat durung loro tapi bar plesiran, tamasya ning wilayah wong sing keno Corona (belum sakit tetapi pulang dari jalan-jalan, bertamasya ke wilayah terdampak corona)
OTG OTG singkatan dari Orang Tanpa Gejala. Maknanya Orang yang terinfeksi Covid-19 namun tidak menunjukkan gejala tertentu
Pada masyarakat Jawa yang diteliti, istilah OTG diplesetkan menjadi Ora Tek Gumun ‘Tidak Begitu Heran’ untuk menanggapi adanya penambahan kasus yang terkena Covid-19, lantaran banyak orang yang kurang begitu mempedulikan protokol kesehatan.
PDP PDP singkatan dari Pasien Dalam Pengawasan, yang
PDP dijelaskan dengan penggambaran lagi pilek, kadang batuk yo mriang mulane dipantau
New Normal, Kajian Multidisiplin | 481
Istilah Covid-19
Maksud dan Maknanya Register-Register Berkaitan
Covid-19 oleh Masyarakat Jawa bermakna seseorang yang memiliki gejala terpapar virus Corona yakni bergejala deman dan atau gangguan pernafasan
(orang yang sedang pilek, terkadang batuk, demam, makanya dipantau keadaannya) Pada masyarakat Jawa istilah PDP diplesetkan menjadi Positip Dadi Pengangguran ‘Positif Menjadi Pengangguran’. Register PDP ala masyarakat Jawa ini menunjukkan bahwa dengan adanya pagebluk covid-19 mengakibatkan banyak pekerja yang di PHK yang bermuara pada bertambahnya jumlah pengangguran
Positif Seseorang yang dalam tubuhnya terpapar adanya virus corona/covid 19
Kena virus ‘terkena virus’, digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut orang yang positif terpapar virus corona/Covid-19, diperjelas dengan kalimat nah sing iki wis di tes karo dokter, wis beneran loro tenan (nah ini yang sudah dites oleh dokter sudah beneran sakit)
Social distancing
Menghindari tempat umum dan keramaian serta menjaga jarak (Jaga Jarak Sosial)
Jaga jarak ‘menjaga jarak’, istilah yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut istilah social distancing. Social distancing dipahami oleh masyarakat Jawa sebagai anjuran untuk ojo kluyuran ning mall, pasar yen ra perlu banget, ora usah ngumpul-ngumpul, nek kepethuk wong jogo jarak 1-2 meter (tidak berpergian ke mall atau pasar jika tidak perlu, tidak perlu mengadakan perkumpulan, kalau berjumpa orang lain harus menjaga jarak 1-2 meter)
Stay at home
Anjuran pemerintah kepada masyrakat untuk tetap berada di rumah atau meminimalisir keluar tumah sebagai upaya pengurangan kasus terpapar adanya virus corona/covid 19.
NOW merupakan register yang digunakan masyarakat Jawa untuk mengganti istilah stay at home ‘tinggal di rumah’ menjadi NOW yang merupakan akronim dari No Omah Wae ‘di rumah saja’ dalam menghadapi adanya pandemic Covid-19. Untuk mencegah penyebaran virus, masyarakat untuk tetap berada di rumah
482 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Istilah
Covid-19 Maksud dan Maknanya
Register-Register Berkaitan Covid-19 oleh Masyarakat Jawa
Work from Home
(WFH)
Anjuran untuk memaksimalkan produktivitas kerja dari rumah guna mengurangi interaksi dengan banyak orang guna mengurangi penyebaran virus corona
WFH, kerja saka omah, kerjane ning omah ojo mangkat kantor, sing ora metu ora entuk duit, sabar sik yo, mugo² ono sing kelingan karo awake dewe sing susah (kerja dari rumah, kerja tidak berangkat ke kantor, yang tidak keluar rumah tidak mendapat uang, sabar dahulu ya, semoga ada yang teringat dengan kita yang sedang kesusahan). Kerja saka omah ‘bekerja dari rumah’ merupakan register yang dipakai oleh masyarakat Jawa yang diteliti untuk mengganti istilah WFH: Work From Home yang artinya bekerja dari rumah dimana para karyawan atau pegawai yang biasanya bekerja di kantor, namun begitu ada pandemic Covid-19 pekerjaan dikerjakan di rumah.
Work from office
(WFO)
Produktif melakukan atau menyelesaikan pekerjaan di kantor dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan selama pelaksanaan WFO.
Kerja na kantor ‘bekerja di kantor’ merupakan bentuk register yang digunakan oleh masyarakat Jawa yang diteliti untuk mencari padanan kata WFO: Work From Office, maksudnya
Jogo tonggo ‘menjaga tetangga’ merupakan gerakan masyarakat
Jawa sebagai upaya untuk menahan bertambahnya kasus Covid-19 dengan pembatasan sosial yang bersifat non PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Konsep ini dalam bentuk penjagaan keamanan melalui program pos kamling di tiap desa atau RT RW, selain itu juga memiliki kepedulian dengan tetangga sekitar. Jimpitan merupakan konsep saling membantu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang diteliti dengan cara membantu tetangga yang terkena dampak adanya pandemik Covid-19. Gerakan yang dilakukan dengan mengirim makanan, kebutuhan sembako, bungkusan sayuran atau uang kepada para tetangga yang perlu dibantu. Lockdown oleh masyarakat Jawa dimaknai sebagai ora entuk mlebu metu ning negoro/wilayah/daerah liyane (tidak boleh keluar masuk di negara atau wilayah atau daerah lainnya). Bahkan masyarakat Jawa menganggap kata lockdown sebagai sebuah akronim dari [16] : L = Lungguh ayem neng omah O = Ora usah kluyuran
New Normal, Kajian Multidisiplin | 483
C = Cukup istirahat K = Kumpul karo keluarga D = Dipepe awake/berjemur O = Olahraga sak cukupe W = Wijik sing bersih N = Ndonga sing diakeh
Penutup
Masyarakat Jawa memiliki bentuk-bentuk register bahasa yang banyak dikenal mengandung pengetahuan dan kearifan lokal. Termasuk dalam menghadapi pagebluk ‘bencana alam’ Covid-19, masyarakat Jawa banyak memunculkan istilah-istilah yang berkaitan dengan itu. Berdasar-kan hasil analisis, munculnya ekspresi verbal berupa bentuk-bentuk register berkaitan dengan pembicaraan seputar Covid berupa plesetan, penggunaan istilah lain dengan bahasa Jawa, dan penggunaan register mengenai Covid 19 apa adanya.
Rujukan
[1] F. Febriyandi YS, “Penanganan Wabah Covid-19 Dengan Pendekatan Budaya,” Indonesiana Platform Kebudayaan, 2020. [Online]. Available: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/. [Accessed: 05-Jul-2020].
[2] R. Junieles and S. F. Arindita N, “Register Kesehatan Era Pandemi Covid-19 dalam Komunikasi di Berbagai Media Online,” Tabasa J. Bhs. Sastra Indones. dan Pengajarannya, vol. 1, no. 1, 2020.
[3] N. Nurdiyani, “Sikap Bahasa Gubernur Ganjar Pranowo dalam Maklumat Gotong Royong Melawan Virus Corona di Masa Pandemi Covid-19,” in Seminar Nasional Hardiknas Belajar dari Covid 19, 2020, pp. 99–106.
[4] R. Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics Fifth Edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
[5] R. A. Hudson, Sociolinguistics (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
[6] B. Spolsky, Sociolinguistics: Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University, 1998.
[7] A. Chaer and L. Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
[8] J. Holmes, An Introduction to Sociolinguistics. London: Routledge,
484 | New Normal, Kajian Multidisiplin
2013.
[9] P. M. Lestari, “Register Pengamen: Studi Pemakaian Bahasa Kelompok Profesi di Surakarta,” Lingua, vol. 6, no. 1, pp. 33–40, 2011.
[10] M. Sudaryanto, Sumarwati, and E. Suryanto, “Register Anak Jalanan Kota Surakarta,” BASASTRA J. Penelit. Bahasa, Sastra Indones. dan Pengajarannya, vol. I, no. April, pp. 514–528, 2014.
[11] H. B. Mardikantoro, Samin Kajian Sosiolinguistik Bahasa Persaudaraan dan Perlawanan. Yogyakarta: Forum (Grup Relasi Inti Media), 2017.
[12] P. M. Lestari, “Karakteristik Gosip Wanita Jawa dalam Interaksi Sosial,” in Mengungkap Budaya Nusantara yang terpendam dalam Kajian Multidisiplin, Bandung: PT. Raness Media Rancage, 2020.
[13] H. S. Ahimsa Putra, “Baik” dan ‘Buruk’ dalam Budaya Jawa-Sketsa Tafsir Nilai-Nilai Budaya Jawa,” Patrawidya, vol. 13, no. 3, pp. 383–409, 2012.
[14] A. Rosidi, “Kearifan Lokal dan Pembangunan Negara,” in International Conference on Traditional Culture and “rAncAge” Award 2010, 2010, pp. 1–10.
[15] F. Damayanti, “Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama,” Madani J. Polit. dan Sos. kemasyarakatan, vol. 12, no. 1, pp. 74–86, 2020.
[16] R. Anshori, “13 Istilah Terkait Covid-19 dalam Bahasa Jawa,” Tagar.id, 2020. [Online]. Available: https://www.tagar.id/13-istilah-terkait-covid19-dalam-bahasa-jawa. [Accessed: 07-Sep-2020].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 487
Bab 31
Sustainability Inovasi UKM di Masa Pandemi Asngadi35 dan Mas’adah36
Pengantar
UKM telah menjadi tulang punggung perekonomian di hampir semua negara. Jumlahnya yang besar menjadikan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang besar. [1], [2]. Sebagai unit ekonomi yang sebarannya meluas hampir di semua geografis, keberadaan UKM menjadi sangat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah. Selain itu keberadaan UKM yang berada di berbagai daerah, menjadikan berbagai UKM menjadi motor penggerak pengelola produk unggulan daerah [3], [4]. Banyak produk unggulan daerah, merupakan hasil kreativitas dan inovasi UKM. UKM yang tumbuh didaerah, umumnya memperoleh dukungan sumber bahan baku dari daerah sekitar. Ketersediaan bahan baku lokal di berbagai daerah di Indonesia menjadikan berbagai UKM bersifat unik, karena aktivitasnya bertalian dengan sumber bahan baku lokal.
Selain sebaran bahan baku, banyaknya jenis bahan baku yang ada di berbagai daerah menstimulasi UKM tumbuh dengan karakter khas lokal. Potensi pengembangan UKM berbasis lokal menjadi ciri dari kalster UKM di Indonesia[5], [6]. Meskipun UKM dalam banyak fakta memberikan nilai nilai tambah positif, namun UKM menghadapi berbagai kendala. Secara umum, UKM memiliki kendala keuangan, operasional, aspek permodalan, hingga pada aspek jangkauan pasar serta masalah kemitraan. Fakta lain yang mengemuka bahwa, meskipun secara kuantitas UKM lebih besar dari usaha besar, namun dilihat dari daya saingnya, UKM masih sangat lemah. UKM yang mampu menembus pasar ekspor masih sangat terbatas, dan umumnya hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Realitas ini memberikan makna bahwa selaian jejaring, kelemahan UKM nampak pada aspek inovasi dan manajerial bisnis, terutama pada pengelolaan bisnis dan manajerial [7]
Akibatnya UKM sulit untuk naik kelas, dan cenderung stagnan dari waktu ke waktu. Meskipun berbagai upaya pemerintah untuk mem-bangun daya saing UKM telah banyak dilakukan, termasuk pemberian
35 Dr. Asngadi Dosen FEB Universitas Tadulako 36 Dr. Mas’adah, STIE K.H Ahmad Dahlan, Lamongan
488 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dukungan pendanaan, namun tidak serta merta UKM akan tumbuh dan berkembang dengan cepat. Peran pemerintah dalam memberikan dukungan pendanaan melalui program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), tidak serta merta daya saing UKM meningkat secara signifikan. Perlu adanya sentuhan dari stakeholder untuk meningkatkan kekuatan UKM dai berbagai aspek. Kolaborasi antara Academic-Business-Governmance (ABG) di banyak negara, mampu memberikan energi bagi UKM untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi antar stakeholder tersebut memungkinkan UKM memperoeh akses yang lebih mudah, dukungan kebijakan dan jaringan kerjasama yang memungkinkan. [8]–[12]
Kolaborasi antar stakheloder menciptakan “enabler” bagi UKM untuk tumbuh dan berkembang, terutama dukungan lingkungan eksternal. Enabler sangat penting bagi UKM untuk tumbuh dan berkem-bang, karena kelemahan UKM secara internal menyebabkan ketidak-mampuan membangun daya saing. Pergerseran lingkungan eksternal secara umum akan menjadi pemicu proses internalisasi bisnis, artinya bahwa setiap perubahan lingkungan eksternal akan menjadi sumber perubahan internal perusahaan. Perusahaan yang mampu dan memiliki kekuatan internal, maka setiap perubahan lingkungan eksternal akan “diinternalisasi” dengan lahirnya strategi dan kebijakan baru, dan menjadi sumber kekuatan baru. Konsep Blue Ocean strategy, secara esensi merupakan ejawantah kemampuan bisnis dalam melahirkan inovasi baru, yang dipicu oleh pergerakan lingkungan eksternal, sehingga “kebaruan” bisnis selalu muncul ditengah gejolak lingkungan eksternal, baik dari pesaing maupun para pendatang baru. [13]–[15].
Selain lingkungan persaingan, fenomena krisis ekonomi global adalah salah satu “enabler” yang memungkinkan pelaku bisnis untuk melakukan perbaikan. Perubahan lingkungan bisnis selalu akan mencip-takan hambatan dan peluang baru. Peluang baru hanya akan muncul jika pelaku bisnis mampu melakukan telaah lingkungan, dan dengan sumber daya internalnya mampu mendesain strategi yang tepat. Ini berarti inovasi dan continuous improvement akan menjadi jawaban atas perubahan lingkungan bisnis.[16], [17]
Fenomena perubahan lingkungan yang berdampak luas di tahuan 2020 adalah meluasnya wabah covid-19, pandemi global yang disebab-kan oleh Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Covid 19 telah berdampak tidak saja pada aspek kesehatan semata. Efek bola salju dari covid 19, merembet dari masalah kesehatan ke masalah
New Normal, Kajian Multidisiplin | 489
ekonomi. Jika pada awal penyebarannya concern pemerintah lebih banyak diarahkan pada aspek kesehatan, namun dalam kurun waktu selanjutnya, lebih banyak di arahkan pada aspek ekonomi. Hal ini mengingat dampak ekonomi yang meluas dari efek domino wabah corona yang tidak kunjung teratasi. [18], [19]. Dampak corona tidak saja dirasakan pada usaha besar, namun skala usaha mikropun terpengaruh oleh wabah ini. Dalam pengalaman krisis tahun 1998 dan krisis global lainnya, dampak dominan hanya dirasakan oleh usaha besar, sementara UKM secara umum relatif tangguh terhadap krisis. Kini, realitas tersebut berbeda, karena efek covid-19, berdampak langsung pada UKM. Berbagai UKM di daerah banyak yang tidak mampu bertahan meskipun dukungan pemerintah melalui restrukturisasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan (perbankan) cukup agresif.
Meski sebagian besar UKM terkena dampak yang luas, namun kemampuan UKM untuk bertahan juga menunjukkan sisinya. Covid 19 yang berkepanjangan, telah menjadikan lingkungan bisnis berubah dengan cepat, termasuk perilaku masyarakat dalam perekonomian. Lingkungan bisnis yang berubah tersebut pada sesi awal covid 19, menjadi pukulan telak bagi UKM, sehingga banyak UKM yang tidak mampu melanjutkan bisnisnya. Kebijakan pemerintah seperti PSBB (pembatasan sosial berskala besar) telah mengubah pasar pada UKM. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan belum adanya tanda tanda berakhirnya covid 19, menjadikan lingkungan bisnis yang tidak menentu tersebut menjadi sesuatu yang “given”. Kondisi ini yang harus disikapi oleh UKM untuk tetap bertahan hidup ditengah pandemi. Dan pada posisi inilah inovasi harus lahir dari UKM untuk tumbuh dan berkembang, dengan lingkungan “new normal”. Tulisan ini seaca khusus bertujuan untuk mengungkap esensi inovasi UKM ditengah pandemi, sebagai lingkungan “baru” yang terbentuk karena wabah corona. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku UKM untuk bertahan ditengah corona? Akankan inovasi yang telah dimulai untuk bertahan di tengah corona akan surut, seiring dengan membaiknya kondisi lingkungan pasca corona?
Pembahasan
Lingkungan bisnis
Lingkungan bisnis menentukan kinerja bisnis, baik bisnis besar maupun UKM. Lingkungan merupakan faktor penentu penting yang diperhitungkan dalam membuat strtaegi bisnis. Dinamika lingkungan
490 | New Normal, Kajian Multidisiplin
eksternal yang berupa threat of new entries, threat of subtitute products, bargaining power of customers,bargaining power of suppliers,intensity of competitive rivalry [20], selalau berdampak pada kondisi internal perusahaan.
Akibatnya perlu penyesuaian lingkungan internal perusahaan berupa alokasi resource, peningkatan capability, serta membangun daya saing melalui pemciptaan dan penguatan core competences menjadi sebuah tuntutan [21]–[23]. Dengan cara yang berbeda, strategi berbasis sumber daya (resources based views) akan menjadi suatu tuntutan bagi pelaku bisnis untuk mampu bertahan dalam konjungtur lingkungan bisnis yang selalu dinamis. [24], [25]
Daya Saing UKM dan Peran Pemerintah
Acuan dan konsep UKM terdapat di beberapa litetarur dan kementerian, dimana tiap literatur memiliki dimensi dan penekanan yang berbeda. Berdasarkan Kementerian Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005 tanggal) uraian UKM sebagai berikut: 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan
WNI, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100 juta per tahun.
2) Usaha Kecil adalah: a) Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau, b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar, milik WNI, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau
3) Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 1999, menjabarkan usaha menengah adalah : a) Kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar, dan c) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.
Selain kriteria diatas, masih terdapat beberapa kriteria lain seperti kriteria BPS (Badan Pusat Statistik) yang mensyaratkan jumlah tenaga kerja 5-19 orang sebagai usaha kecil, sementara usaha dengan jumlah tenaga kerja berkisar 20-99 orang, sebagai usaha menengah. UU No 20 Tahun 2008 juga memberikan penguatan tentang pengertian UKM, yang didasarkan pada kekayaan bersih usaha. Berdasarkan karakteristik tersebut, jumlah UKM di Indonesia mencapai 58,97 juta di tahun 2018,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 491
dan kontribusinya terhadap total ekspor kurang dari 10 persen [26]. Ini berati bahwa sebagian besar UKM masih memerlukan pembinaan yang luas untuk membangun daya saingnya.
Daya saing UKM yang rendah merupakan akumulasi dari berbagai problematika yang mendera UKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara umum, karakteriistik UKM identik dengan usaha yang memiki kendala cukup menonjol pada aspek manajerial, operasional, hingga jaringan [2]. Secara umum bahwa kendala yang dihadapi UKM adalah kesulitan bahan baku 8,592 %; tenaga kerja 1,093%; kesulitan transportasi 0,224 %; kesulitan pemasaran, 34,725 %, permodalan 51,096 %, lainnya. 3,93%. [27]
Meski demikian, potensi UKM untuk tumbuh menjadi pelaku ekonomi global juga terbuka luas. Namun karena kodisi internal yang membelenggu, akhirnya peluang tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Peran pemerintah dalam melakukan internasionalisasi UKM juga dirasakan belum optimal [27]. Selain itu adanya overlapping kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terkadang justru menciptakan kerumitan dalam pengembangan UKM [28]
Pentingnya keberadaan UKM pada satu sisi serta banyaknya masalah yang dihadapinya pada sisi yang lain, memberikan makna pentingnya upaya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan bahwa UKM tetap tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional [14]. Salah satu bentuk program pengembangan UKM di Indonesia adalah program Community Development melalui BUMN, yaitu sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan investasi sosial jangka panjang [29]. Upaya pemerintah lainnya dalam pengembangan UKM dapat dilihat dari banyaknya bantuan yang digulirkan bagi UKM.
Berbagai dukungan pemerintah dalam penembangan UKM juga terus berlanjut, dan hingga kini masih banyak bantuan yang diperuntukkan untuk menumbuhkan UKM, diantaranyua adalah KUR ( kredit usaha rakyat) meskipun derajat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan[30], [31]. Pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan UKM setidaknya didasarkan pada 3 alasan utama [32] yaitu: 1) UKM meningkatkan kompetisi dan enterpreneurship, oleh karenanya
UKM memiliki dampak positif terhadap efisiensi ekonomi secara luas, inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dalam perspektif ini,
492 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pengembangan UKM akan membantu negara dalam mengekploitasi manfaat sosial dari tingginya kompetisi dan enterpreneurship tersebut.
2) UKM dalam banyak kasus, umumnya lebih banyak yang produktif dibanding yang gagal, namun pasar keuangan dan berbagai institusi lainnya tidak selalu mendukung pengembangan UKM. Jadi, dukungan keuangan pemerintah bagi UKM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perekonomian.
3) Peningkatan UKM lebih besar dampaknya dibanding perusahaan besar karena sifatnya yang labour intensive. Dari perspektif ini, maka pengembangan UKM akan berfungsi sebagai alat mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Tabel 1: Proporsi Bantuan Dalam Pengembangan UKM (persen)
Sumber: SMERU, 2004 dalam Tambunan 2008.
Meskipun peran UKM dalam perekonomian nasional cukup besar, baik dalam penyiapan lapangan kerja maupun pengelolaan produk unggulan daerah, namun daya saing UKM secara umum masih lemah. Menyadari pentingnya UKM ini dan melihat sisi lemahnya, maka peran pemerintah menjadi amat penting dalam membangun daya saing UKM. UKM yang berdaya saing akan menjadi lokomotif perekonomian negara [33]–[35]. Bagi UKM itu sendiri, daya saing harus selalu dibangun melalui upaya sistematis dan realistik melalui berbagai pola, diantaranya harus secara proaktif membangun kekuatan pada segmen yang baru, penguatan jiwa kepemimpinan, pengambilan keputusan berbasis data, memahami bahwa resiko berbanding lurus dengan return, fokus pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan tidak risau dengan kegagalan di masa lalu [19]
Penguasaan teknologi saat ini menjadi sebuah keharusan bagi bisnis, termasuk UKM. Akses teknologi yang makin murah dan jangkau-an teknologi yang telah meluas di masyarakat menjadikan perluasan pasar melalui jejaring semakin mudah, tepat dan efisien [36]–[38]. Studi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 493
di Eropa menunjukkan bahwa lebih dari 50% produktivitas dicapai melalui investasi di bidang Teknologi informasi. Pemanfatan teknologi bagi UKM memungkinkan pencapaian daya saing global melalui sistem operasi bisnis yang reliable, seimbang dan berstandar tinggi. [39]. Pemanfaatan teknologi terkini dan perluasan jaringan pasar bagi UKM dalam janghka panjang akan memberikan manfaat bagi UKM untuk mengembangkan inovasi dan pada akhirnya berdampak pada pening-katan daya saing. [36]–[38]. Untuk itu menurut [40] membangun daya saing, UKM dapat dilakukan dengan 3 pola yaitu : a) Adanya inovasi dan perbaikan teknologi yang terus menerus menuju penurunan biaya; b) Pengembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan penghematan waktu, dan c) Pemanfaatan jaringan kerjasama untuk pengembangan pasar secara meluas.
UKM sebagai lembaga ekonomi yang bergerak pada level bawah, umumnya tumbuh secara sporadis dan bahkan keberadaanya tidak berpola. Sebagian usaha kecil berbentuk klaster yang mengelompok pada wilayah geografis tertentu [41], [42]. Sebagai bentuk usaha yang tumbuh alami dalam sekelompok komunitas, maka kelemahan-kelemahan yang menyelimuti UKM juga reatif banyak. Pendekatan pengembangan UKM dengan berbagai karakteristik dan lokasi yang menyebar tidaklah mudah. Oleh karenanya klaster merupakan satu pendekatan yang relatif efektif. Pendekatan ini memungkinkan adanya “homogenitas” karakter UKM, minimal pada aspek perwilayahan, sehingga treatment yang diberikan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya akan lebih terfokus dalam membangun daya siang UKM. Penyediaan sarana dan lembaga pendukung akan mempercepat tumbuhnya daya saing UKM dalam klaster [34], [43], [44].
Inovasi UKM di Tengah Pandemi, Akankan Berlanjut?
Proses perbaikan terus - menerus (continuos improvement) bagi setiap bisnis adalah sebuah keniscayaan, termasuk UKM. Lingkungan bisnis yang selalu bergerak dinamis, mengharuskan inovasi harus selalu dilakukan untuk membangun desain strategi baru yang membangun daya saing bisnis. Covid 19 yang telah merubah lingkungan bisnis dalam waktu yang singkat, membuat para pelaku bisnis stagnan pada fase awal. Adanya aturan PSBB menjadikan semua aktivitas fakum, dan cenderung berhenti. Perusahaan besar sebagian melakukan penyesuaian operasi melalui sistem rolling, pembatasan jam kerja. Strategi operasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran covid di satu sisi.
494 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Dari sisi bisnis, pembatasan jam operasi ini, sesungguhnya adalah upaya penyesuaian agar perusahaan tetap dapat mempertahankan operasinya pada level minimal, yang mampu menutup biaya operasi dalam jangka pendek. Hal ini selaras dengan temuan [45], [46], bahwa UKM setidaknya melakukan proses inovasi pada aspek keuangan, pemasaran dan isu isu manajemen. Pada intinya pandemi covid 19 mengharuskan adanya redesain strategi baru yang mampu menghidupkan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang [47].
Secara teknis inovasi pemasaran dilakukan tidak saja dilakukan saat ini (masa pendemi), untuk memecahkan masalah sesaat saja, namun juga dapat digunakan untuk mengatasi krisis serupa yang akan terjadi di masa mendatang [48]. Hal serupa diutarakan oleh [49], bahwa pandemi covid 19 tidak hanya berdampak pada pada aspek pemasaran alam arti luas, namun juga pemasaran dalam arti strategik. Pada tataran praktek, inovasi pemasaran yang banyak dilakkan oleh UKM dapat berupa perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. [50]. Temuan lain juga menekankan pentingnya pengurangan beban biaya dalam sistem distribusi, yang berarti bahwa perusahaan perlu melakukan pengurangan biaya yang ditanggung oleh pelanggan maupun yang ditanggung perusahaan. Pemanfaatan jasa pengahantaran produk merupakan salah satu alternatifnya[51].
Covid 19 yang merubah peta bisnis dalam waktu singkat, memaksa pelaku bisnis untuk mereformulasi kembali bisnis mereka, termasuk pengembangan bisnis baru, baik yang memiliki lini produk sebelumnya maupun tidak. Ini menggambarkan bahwa pelaku bisnis UKM memiliki derajat fleksibilitas yang tinggi dalam melakuan desain dan perancangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Beberapa produk kesehatan (masker, APD) banyak yang dihasilkan oleh UKM yang sebelumnya bergelut di sektor kuliner, maupun sektor lainnya yang tidak terkait dengan alat kesehatan merupakan contoh nyata inovasi produk yang tidak satu lini[52]. Selain itu, inovasi yang terkait lini produk masih dimungkinkan, karena di masa pandemi perilaku konsumsi masyarakat juga berubah. Industri rumah makan, dapat mengembangkan produk bumbu makanan sebagai turunan produk dari industri serupa (satu lini). Inovasi produk yang tidak terkait dengan pengalaman sebelumnya menggambarkan kuatnya jiwa kewirausahaan pelaku bisns UKM. Kekuatan kewirausahaan ini menjadikan pelaku UKM berani meng-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 495
ambil resiko, kemampuan melakukan adaptasi secara cepat dan mampu membaca peluang saat fenomena perubahan lingkungan berubah dengan cepat [53], [54].
Untuk mampu mempertahankan bisnis UKM ditengah covid, maka kekuatan pasar dalam negeri harus diperkuat. Ini berati perlu adanya kohesi antar pelaku bisnis di dalam negeri, ditengah lemahnya iklim perdagangan luar negeri [55]. Dari aspek perilaku keuangan, perlu adanya penguatan melalui resolusi keuangan, yang tidak lain adalah melakukan redefinisi derajat prioritas, secara terukur dan realistik. [55], [56]. Pada tataran akhir, aspek sumber daya manusia harus menjadi prioritas jangka pendek bagi UKM untuk tetap bertahap di tengah pandemi. Fenomena PHK dan merumahkan karyawan adalah bagian dari upaya yang dilakukan UKM untuk bertahan hidup ditengah pandemi. Tercatat, hingga Agustus 2020, jumlah PHK secara nasional mencapai 5,23 juta pekerja [57]
Sebagai strategi bertahan bagi UKM, pengurangan jam kerja, sistem rolling, pemotongan gaji juga merupakan bagian dari mempertahankan karyawan perusahaan. Dengan pola ini, maka jumlah karyawan diperusahaan akan dapat dipertahankan, dengan beban finansial yang realistik [58]. Meski demikian, fenomena ini menjadi kendala finansial karyawan karena adanya penurunan pendapatan. Selain upaya internal pelaku bisnis UKM, upaya eksternal untuk mempertahankan kehidupan bisnis, pemerintah juga memberikan berbagai dukungan yang cukup signifikan. Dari aspek ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, subsidi tunai bagi pekerja merupakan salah satu alternatif jangka pendek yang memungkinkan pelaku usaha tidak melakukan PHK. [59]
Untuk mempertahanakan kontinitas produksi, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM melakukan berbagai aktivitas pemantauan keter-sediaan bahan baku, bantuan desain, bantuan permodalan dan fasilitasi pemasaran [52], [53]. Asilitasi migrasi digital pelaku usaha dalam pemasaran produk juga banyak dilakukan oleh BUMN melaui pasar digital. Dengan pola ini, maka BUMN menjadi fasilitator bagi pelaku UKM untuk melakukan proses bisnis secara online dengan platform yang dikembangkan oleh BUMN. [18], [59]. Pola ini bermakna bahwa secara internal pelau UKM melakukan berbagai inovasi dengan sumber daya yang dimiliki, dan secara eksternal pemerintah menciptakan ruang bagi UKM untuk mendapatkan kemudahan dalam pengembangan bisnis di tengah pandemi covid 19, melalui berbagai kebijakan, strategi, dan fasilitasi.
496 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Penutup
Berdasarkan pada paparan dan telaah realitas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut: 1. Covid 19 telah merubah tatahan kehidupan, baik dari perspektif
kesehatan maupun bisnis, yang berdampak tidak saja pada usaha besar, namun juga berdampak pada UKM.
2. Covid 19 telah menciptakan konjungtur lingkungan ekonomi yang sangat cepat, sehingga dalam jangka pendek pelaku usaha UKM stagnan sejenak, lalu kemudian meredesain strategi bisnis yang digeluti.
3. Teknologi yang berkembang saat ini menjadi rambatan bagi UKM untuk melakukan inovasi bisnis, sehingga percepatan inovasi UKM ditunjang oleh perkembangan teknologi digital saat ini.
4. Inovasi UKM untuk bertahan di masa covid 19 meliputi semua aspek fungsi manajemen yakni inovasi produk, inovasi dalam pemasaran, inovasi dalam sistem keuangan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia.
5. Covid 19, menjadi trigger bagi inovasi UKM dan akan tetap menjadi kekuatan bisnis internal di masa “new normal” dan pasca covid di masa mendatang, dan menjadi bagian dari strategi bisnis pada lingkungan serupa di masa mendatang.
6. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi lelalui berbagai stimulus dan fasilitasi, menciptakan lingkungan ekternal yang mem-percepat keberhasilan inovasi internal dalam mepertahankan bisnis UKM.
Rujukan
[1] M. . J. Hafsah, “Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM,” J. infoskop, 2004.
[2] D. C. Lantu, M. S. Triady, A. F. Utami, and A. Ghazali, “Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model,” J. Manaj. Teknol., 2016, doi: 10.12695/jmt.2016.15.1.6.
[3] Sunoto, “Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia,” tata ruang online Bull. ISSN1978-1571, 2007.
[4] F. Sukesti and S. Iriyanto, “Pemberdayaan Ukm : Meningkatkan Komoditas Unggulan Ekspor Ukm Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Daerah (Studi pada UKM di Jawa Tengah),” Pros. Semin. Nas. Int., 2011.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 497
[5] T. Tambunan, “Export-oriented small and medium industry clusters in Indonesia,” J. Enterprising Communities, vol. 3, no. 1, pp. 25–58, 2009, doi: 10.1108/17506200910943661.
[6] S. Badri, “Proses Keputusan Dengan Metode AHP (Aplikasi Model untuk Menggembangkan Klanster Agroindustri Kelapa Sawit),” no. 42, pp. 1–16, 2011.
[7] I. Kamil and I. Hapsari, “Pengembangan Model Industri Kelautan Berbasis Klaster Di Kota Padang,” pp. 87–92, 2004.
[8] T. M. T. C. Rodrigo, U. I. K. Galappaththi, K. P. K. S. Shanka, W. R. N. Gunarathna, J. H. J. S. De Silva, and K. G. L. Samarawansa, “Technology Transfer Solutions for SMEs in Sri Lanka through University-Industry Collaboration,” 2019, doi: 10.1109/POMS.2018.8629396.
[9] M. Saqib, Z. M. Udin, and R. Zarine, “Exploring the technology orientation influence on the innovativeness-performance relationship of manufacturing SMEs,” Int. J. Innov. Learn., 2018, doi: 10.1504/ijil.2018.10015245.
[10] C. Els, S. Grobbelaar, and D. Kennon, “Redefining the role of SMEs in value creating ecosystems: Evidence from case studies,” 2018.
[11] M. del P. Casado-Belmonte, G. M. Marín-Carrillo, E. Terán-Yépez, and M. de las M. Capobianco-Uriarte, “What is going on with the research into the internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)? An intellectual structure analysis into the state-of-the-art (1990-2018),” Publications, 2020, doi: 10.3390/publications8010011.
[12] A. Sumaili, N. Dlodlo, and J. Osakwe, “Adopting Dynamic Capabilities of Mobile Information and Communication Technology in Namibian Small and Medium Enterprises,” 2018, doi: 10.1109/OI.2018.8535941.
[13] D. Irawati, “Strengthening Cluster Building in Devleoping Country alongside the Triple Helix: Challenge for Indonesian Clusters-A Case Study of the Java Legion,” no. 39944, 2012.
[14] Asngadi and Mas’adah, “Industrialization of Small Medium Enterprises,” vol. 231, no. Amca, pp. 186–189, 2018, doi: 10.2991/amca-18.2018.51.
[15] Y. V. Reddy and S. S. Naik, “Determinants of goan SME firms going global: Theoretical and empirical approach,” Vikalpa, vol. 36, no. 2, pp. 45–58, 2011, doi: 10.1177/0256090920110204.
[16] U. E. Gattiker, “Continuous Improvement,” in SpringerBriefs in
498 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Computer Science, 2013.
[17] Y. Nauwelaerts and I. Hollaender, “Innovation Management of SMEs in the Creative Sector in Flanders and the Netherlands,” J. Mark. Dev. Compet., vol. 6, no. 3, pp. 140–153, 2012.
[18] Tempo, “Luncurkan Pasar Digital, Perusahaan BUMN Penuhi Barang dan Jasa dari Produk UMKM,” Tempo.co, Jakarta, Aug. 2020.
[19] Kompas, “Cara Meningkatkan Daya Saing Bisnis,” KOmpas Gramedia, Jakarta, Aug. 2020.
[20] M. E. Porter, “The five competitive forces that shape strategy,” Harv. Bus. Rev., 2008.
[21] K. Ayuwuragil, “Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online,” CNN Indonesia, 2017. .
[22] M. L. Martens and M. M. Carvalho, “Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers’ perspective,” Int. J. Proj. Manag., 2017, doi: 10.1016/j.ijproman.2016.04.004.
[23] J. Treble, “Why behaviour change matters,” Green Consult., vol. 50, no. 2, pp. 257–282, 2017, [Online]. Available: https://www.greenconsultancy.com/discover-total-energy-management/implementing-energy-efficiency-opportunities/energy-training-and-behaviour-change.
[24] F. Simangunsong, I. Hutasoit, and I. Sentosa, “A strategic framework of good governance, infrastructure development and community empowerment in indonesian public sector management,” African J. Hosp. Tour. Leis., 2019.
[25] Wahyuningsih, Husnah, R. Dg, Rahmatu, and Asngadi, “Strategic Management, Competitive Advantage and Community Empowerment,” 2019, doi: 10.2991/iccd-19.2019.157.
[26] UKMC, “Penyesuaian skala usaha ukm ekspor,” Jakart, 2018. [Online]. Available: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-zMPg4cXrAhWQf30KHfczAkEQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.indonesiaeximbank.go.id%2Fresearch%2Fdownloads%2F6&usg=AOvVaw0Jo6cykevHGHQd2mUAXygO.
[27] I. Cahyadi, “Tantangan internasionalisasi UKM di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN,” J. Akunt. dan Manaj., 2015.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 499
[28] D. Wuryandani, “Peranan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” J. Ekon. dan Kebijak. Publik, 2013.
[29] P. Wahyuningrum, A. Sukmawati, and L. Kartika, “Peningkatan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kluster Kerajinan di Kota Depok Menggunakan The House Model,” J. Manaj. dan Organ., 2016, doi: 10.29244/jmo.v5i2.12156.
[30] D. Anggraini and S. Nasution, “PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI),” J. Ekon. dan Keuang., 2013.
[31] V. W. Sujarweni and L. R. Utami, “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta),” J. Bisnis dan Ekon. (JBE), 2015.
[32] M. Perry and T. T. H. Tambunan, “Re-visiting Indonesian cases for cluster realism,” J. Enterprising Communities, vol. 3, no. 3, pp. 269–290, 2009, doi: 10.1108/17506200910982028.
[33] J. M. Gonçalves, F. A. F. Ferreira, J. J. M. Ferreira, and L. M. C. Farinha, “A multiple criteria group decision-making approach for the assessment of small and medium-sized enterprise competitiveness,” Manag. Decis., 2019, doi: 10.1108/MD-02-2018-0203.
[34] G. Kutnjak, D. Miljenović, and A. Mirković, “Improving competitiveness of small and medium-sized enterprises with the application of quality management system,” Pomorstvo, 2019, doi: 10.31217/p.33.1.2.
[35] A. Kukharuk and J. Gavrysh, “Competitiveness of smes in terms of industry 4.0,” 2019, doi: 10.1109/CREBUS.2019.8840103.
[36] A. Nuvriasari, “Model Strategi Peningkatan Daya Saing UKM Industri Kreatif Berbasis Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan,” Semin. Nas., 2015.
[37] E. Supeni, “Penerapan Model Triple Helix Dan Keunggulan Bersaing Pada Ukm Industri Kreatif Di Kabupaten Sidoarjo,” Pros. Konf. Nas. Pengabdi. Kpd. Masy. dan Corp. Soc. Responsib., 2019, doi: 10.37695/pkmcsr.v2i0.444.
[38] S. Suhartini and E. Ismiyah, “Pengembangan Variabel Model Kinerja dan Daya Saing Klaster Industri Batik,” 2016.
[39] A. Rahmana, “Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah,” Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf.
500 | New Normal, Kajian Multidisiplin
2009 (SMATI 2009), 2009.
[40] M. Kristiyanti, F. Ekonomi, and U. Aki, “Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia,” vol. VOL 2, 2011.
[41] M. A. Mukhyi, “KAWASAN EKONOMI PROPINSI JAWA BARAT Pendekatan Analisis IRIO,” Ekon. Dan Keuang., vol. 1, no. 6, pp. 32–48, 2013, doi: https://scholar.google.co.id/scholar.
[42] Widyastutik, H. Mulyati, and E. I. K. Putri, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Klaster UMKM Alas Kaki di Kota Bogor yang Berdaya Saing,” Manajemen dan Agribisnis, vol. 7, no. 11. pp. 16–26, 2010.
[43] C. Taçoğlu, C. Ceylan, and Y. Kazançoğlu, “Analysis of variables affecting competitiveness of smes in the textile industry,” J. Bus. Econ. Manag., 2019, doi: 10.3846/jbem.2019.9853.
[44] S. Siriphattrasophon, “Multi-level factors affecting firm competitiveness in ASEAN region of small and medium enterprises of Thailand,” Kasetsart J. Soc. Sci., 2019, doi: 10.1016/j.kjss.2017.09.002.
[45] F. Eggers, “Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs in times of crisis,” J. Bus. Res., 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.05.025.
[46] A. Susanti, B. Istiyanto, and M. Jalari, “SMEs Strategy at Covid-19 Pandemic,” Kangmas, vol. 1, no. 2, 2020.
[47] S. Hadi and S. Supardi, “SMEs Strategy at Covid-19 Pandemic,” J. XI’AN Univ. Archit. Technol., 2020, doi: 10.37896/jxat12.04/1149.
[48] Y. Wang, A. Hong, X. Li, and J. Gao, “Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19,” J. Bus. Res., 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.05.029.
[49] H. He and L. Harris, “The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy,” J. Bus. Res., 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.05.030.
[50] W. laura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19,” J. Akunt. dan Ekon., 2020, doi: 10.37859/jae.v10i1.1934.
[51] F. Hardiyanto, “Analisis marketing Syariah dalam menghadapi covid 19 (studi kasus ARPI hijab Kuningan),” J. Syantax Admiration, 2020.
[52] E. Widianto, “Inovasi UMKM di Tengah Pandemi COVID-19,” Terakota.id, 2020.
[53] A. A. V. dan T. R. D. A. Nugroho, “Intensi Kewirausahaan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 501
Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura,” Agriekonomika, 2015. [54] S. Wanhill, “Small and medium tourism enterprises,” Ann. Tour.
Res., 2000, doi: 10.1016/S0160-7383(99)00072-9. [55] A. Djafar, “Tetap Sehat Mental dan Finansial di Tengah Pandemi,”
Gatra, Jakarta, 2020. [56] C. Albulescu, “Coronavirus and Financial Volatility: 40 Days of
Fasting and Fear,” SSRN Electron. J., 2020, doi: 10.2139/ssrn.3550630.
[57] B. P. Siregar, “Jumlah PHK Bakal Tembus hingga 5,23 Juta Orang, Kemenaker Siapkan...,” Warta ekonomi, Jakarta, Aug. 2020.
[58] A. Fahmi, “https://www.idxchannel.com/market-news/strategi-tiga-perusahaan-hindari-phk-dan-tetap-beri-gaji-di-tengah-pandemi,” IDX, Jakarta, 2020.
[59] L. Mustinda, “Subsidi Gaji Karyawan dan Program Kartu Prakerja, Ini Perbedaannya,” Detikfinance, Jakarta, Aug. 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 503
Bab 32
Hentakkan Kata Merdeka Pemberdaya Masyarakat Masa Pandemi Covid 2019 Dian Eka Chandra Wardhana37
Pengantar
Masa pandemi virus corona 2019 di Indonesia telah mengubah tatanan dan budaya baru masyarakat Indonesia [1]. Tatanan dan budaya baru masyarakat Indonesia ini meliputi segala macam aspek kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, termasuk tatanan baru yang berdampak cukup signifikan di dunia pendidikan. Hal ini didukung oleh fakta yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo [2], bahwa Covid 19 telah menyerang 255 negara termasuk Indonesia. Fakta tersebut tidak saja merupakan krisis kesehatan publik, namun meru-pakan krisis multifaser, karena berdampak buruk terhadap pendidikan [3]. Berbagai surat edaran untuk mengantisipasi penyelamatan untuk terhindar dari penyebaran penyakit tersebut dari kalangan akademisi [4] dan [5] dari kalangan sekolah, institusi pemerintah dan sekolah membanjiri kehidupan bangsa agar Kerja dari rumah (Work From Home). Dampaknya, berbagai istilah baru bermunculan di dunia kehidupan bangsa. Istilah yang paling terkenal adalah WFH (work from home), WFO (work from office), sabun khusus cuci tangan (hand sanitisier), jarak social (social distance), pandemi (wabah), pernikahan masa covid (drive tru), PSBB dan satu lagi yakni kata merdeka.
Kata ini begitu sangat popular saat ini, kalua dulu sebelum 2020 kata merdeka hanya kita jumpai dalam konteks 17 Agustus, dan popular dengan berbgai hal yang berhubungan dengan hal tersebut, namun berbeda dengan kata merdeka di 2020. Begitu juga kegiatan pembelajaran di sekolah dengan berbagai aspeknya muncul, karena guru yang biasanya bertemu dan bertatap muka dengan siswa menjadi berubah peran. Guru yang semula menjadi pengajar dan pendidik, kini hanya berperan sebagai fasilitator. Walau peran sebagai fasilitator tersebut, berdasarkan diskusi yang dilakukan melalui chat dengan grup alumni IKAL ALUMNI Progam Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unib dan WAG Pelatihan HOTs Rejang Lebong [4] sangat signifikan, karena guru sekarang tidak hanya berperan sebagai pendidik
37 Dr. Dian Eka Chandra Wardhana, FKIP Universitas Bengkulu
504 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dan fasilitator saja tetapi juga menjadi penggerak untuk siswa dan guru lain agar mereka bisa saling contek untuk kemajuan bersama.
Peran guru di masa pandemic ini melaksanakan kegiatannya dengan media yang sangat beragam, namun 80% kegitan pembelajaran daring dilakukan melalui Watch Up (WA). Kegiatan ini tampaknya merata terjadi di Indonesia, karena kegiatan pembelajaran dengan media ini sempat terekam dan dipublikasikan oleh seorang nara sumber [7] . Hal ini harus disyukuri karena banyak siswa yang gak punya android, kuota ataupun listrik sehingga kurun waktu pertengahan april kegiatan pembelajaran dilakukan secara terjadwal melalui TVRI [8]. Bisnis pendidikanpun bermunculan, karena ada pihak swasta yang berminat untuk mengantisipasi kegiatan pendidikan agar kegiatan pendidikan tetap sesuai dengan tujuan pendidikan seperti yang telah ditetapkan UU. Bisnis yang muncul saat itu adalah ruang guru dan yang lainnya. Istilah-istilah yang muncul adalah pembelajaran daring, e-learning, e-book, e-modul, metode Asinkron, dan sinkron, dengan pemberdayaan berbagai aplikasi seperti zoom, bitly, dan masih banyak lagi. Muncul kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat, seperti sholat bawa sajadah sendiri, sholat dengan menggunakan jarak, menggunakan masker dan masyarakat terkesan “sombong” karena tak bisa lagi bersalaman (kalau terpaksa salaman menggunakan sikutnya), tak lagi “cipika-cipiki”, berpelukan bahkan tersenyum karena mukanya tertutup masker. Mayarakat hanya bisa berdiam diri di rumah dengan berbagai aktivitasnya untuk bisa bekerja dan belajar dari rumah. Selanjutnya muncul berbagai macam istilah yakni hand sanitizer = penyitasi tangan, lockdowm=karantina wilayah, psysical distancing=pembatasan fisik, pandemi = wabah, work from home=kerja dari rumah (KDR), social distancing=pembatasan sosial, disinfektan=bahan kimia yang disemprot-kan ke suatu permukaan benda agar benda tersebut higienis (bersih dan betul betul bersih) agar terbebas dari paparan virus corona, bahkan manusia dianjurkan untuk sering cuci tangan agar merdeka dari virus tersebut.
Selanjutnya muncul istilah-istilah baru yang sangat mentereng: webinar (seminar dengan Web), dan belakangan ketahuan bahwa webinar [9] adalah sebuah merk dagang sehingga kangan masyarakat akademisi lebih suka menggunakan istilah seminar dalam jaringan dan lebih sering disingkat dengan nama sedaring. Istilah-istilah lain bermuncullan misalnya host, prank, e-sertifikat, herd imunity, modar (bhs Jawa), terserah, ambyar (bhs Jawa), sakkarepmu (bhs Jawa), fatwa MUI,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 505
pahlawan medis, pahlawan co virus 19 (karena di rumah saja dan tidak mudik [10], dan istilah yan lain seperti PSBB (yang kemudian diplesetkan dengan istilah lain yang lebih keren oleh Kanal Pengetahuan UGM dan masyarakat) [11]. Plesetan-plesetan PSBB ini kemudian dikenal dengan istilah baru yang lebih keren seperti; (1) Pemerintah Sukanya Basa- Basi, (2) Pembatasan Sosial Bokis-Bokis, (3) Penyebaran Virus Secara Besar-Besaran, (4) Penyesatan Soal Bansos dan BPJS, (5) Peraturan Sering Banget Berubah, dan (6) Pelajaran Sejarah Bangsa Bangsa. Istilah-istilah tersebut sangat mungkin bertambah, karena bahasa adalah alat komunikasi yang interaktif dan transaktif. Di samping itu bahasa Indonesia sangat dinamis sesuai dengan alur perkembangan pikir masyarakat penggunannya yang sangat kreatif dan inovatif sehingga perkembangan istilah mengikuti perkembangan cara berpikir masyarakat penggunanya. Hal ini didukung oleh peribahasa dalam Bahasa Indonesia yang sangat terkenal, yakni Bahasa Menunjukkan Bangsa [12]. Berdasarkan fenomena tersebut muncul suatu permasalahan: bagaimanakah hentakkan kata merdeka pemberdaya masyarakat di masa pandemi Covid 19 ?
Metode penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan partisipasi non partisipatif dan partisipasi aktif melalui Webinar, Wach Ap (WA GROUP), Telegram dan Instagram, Youtube, dan menggunakan mesin pencarian (search) untuk kata merdeka di berbagai Surat Edaran yang beredar di Google. Pengumpulan data menggunakan catatan lapangan deskriptif dan reflektif, dan pemilihan sampel secara purposive. Subyek penelitian berjumlah 7 orang, 5 orang guru besar dan 2 orang Lektor Kepala. Hasil percakapan yang telah ditranskripsikan dalam bentuk teks, kemudian dianalisis dengan aplikasi NVIVO. Percakapan yang berhasil ditranskripsikan tersebut berasal dari percakapan antara peneliti dengan Koordinator di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP universitas yang ada di Pesisir Barat Sumatra (Unib, Unsri, Unp, Universitas Negeri Jambi, Umb, Universitas Ratu Samban, IAIN Bengkulu, IAIN Curup, Universitas Patpetulai/Lebong, Uhamka (Padang), Universitas Mochamdyah Padang, Universitas Mochmadiyah Jambi, Universitas Mochamdyah Bengkulu). Selain hal tersebut, data penelitian ditranskipsikan juga dari hasil rekaman, yang dilakukan dengan cara menyimak secara partisipatori dan nonpartisipatori, serta pengisian angket dan catatan lapangan.
Analisis data menggunakan langkah langkah (1) transkripsi data dengan menggunakan aplikasi yang ada android SAMSUNG A8. Langkah-langkah transkripsi yang dimaksudkan [13] adalah; (1) buka
506 | New Normal, Kajian Multidisiplin
percakapan pada chat responden. (2) klik titik 3 (...) pada bagian atas sebelah kanan, setelah keluar menunya, klik option LAINNYA. (3) pilih EXPORT CHAT, (4) klik SERTAKAN MEDIA, (5) klik e-mail, lalu masukkan email yang akan dituju.
Setelah melakukan kegiatan transkripsi dengan teknik seperti tersebut, langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengguna-kan teknik analisis dengan teknik NVIVO [14], teknik analisis data ini sudah digunakan oleh sekitar 400 orang peneliti di 20 negara [15]. Teknik analisis data yang dimaksudkan adalah; (1) Membuka jendela pencarian (peneliti menggunakan google chrome), selanjutnya menginstal aplikasi Ncapture for Nvivo dengan cara klik titik 3 pada bagian atas sebelah kanan cendela google chrome.
(2) Pilih more tools dan klik extensions.
1. Kemudian ketik Ncapture lalu aktifkan dengan cara mengklik
tombol aktif (pastikan terlebih dahulu PC telah terinstal NVIVO).
New Normal, Kajian Multidisiplin | 507
(3) Setelah Ncapture for Nvivo aktif, lalu mencari berita terkait kampus merdeka di pencarian google, kemudian buka jendela berita, lalu klik logo Ncapture for Nvivo yang berada pada bagian atas sebelah kanan.
(a) Lalu klik Article As PDF, selanjutnya klik Capture, dan tunggu
hingga proses download selesai.
Sedangkan data dalam bentuk video tentang kampus merdeka
didapat dari Youtube yang dimulai dengan mencari video terkait, selanjutnya didownload dengan Ncapture seperti langkah data berita.
Setelah data penelitian yang meliputi percakapan whatsap, surat edaran tentang kampus merdeka, berita online tentang kampus merdeka dan video youtube tentang kampus merdeka terkumpul maka dilanjut-kan dengan analisis menggunakan program NVIVO (pastikan PC terkoneksi dengan internet). Analisis dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
508 | New Normal, Kajian Multidisiplin
(1) Membuka aplikasi NVIVO, selanjutnya pilih Nvivo Pro atau
Nvivo Plus (peneliti menggunakan Nvivo Plus) lalu klik Launch Nvivo.
(2) Tunggu beberapa saat sampai jendela program Nvivo terbuka. Setelah itu pilih Blank Projek.
(3) Lalu ketikkan judul/nama dokumen kerja pada kolom title, kemudian klik Ok.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 509
(4) Setelah jendela kerja terbuka langkah pertama yang dibuat adalah dengan membuat folder kerja dengan cara klik kanan pada menu file, lalu klik New Folder.
(5) Kemudian ketikkan nama foldernya sesuai format data, dalam
penelitian ini bentuk data ada 3 jenis yaitu MS Word, PDF, dan Video. Pada folder pertama pada kolom name diketik dokument word, lalu klik Ok.
510 | New Normal, Kajian Multidisiplin
(6) Selanjutnya ulangi langkah yang sama dengan memasukkan nama dokument PDF dan dokumen Video.
Setelah folder siap, maka data siap di input ke dalam Nvivo.
Untuk data dalam bentuk MS word (hasil percakapan Whatsap) dimasukkan dengan cara sebagai berikut :
(1) Klik file lalu pilih dokument word selanjutnya klik kanan pada jendelah kosong dan pilih Exsport List.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 511
(2) Lalu cari file data selanjutnya blok semua data yang akan kita masukkan dan klik Save.
(3) Lalu klik Import. Tunggu sampai semua data kita terimport pada jendela kerja.
Untuk data surat edaran dimport dengan langkah kerja yang sama dengan data percakapan whatsap namun pada folder dokument PDF dan atau video. Untuk data berita online diimport dengan cara sebagai berikut : (1) Klik pada menu folder dokument PDF dan atau Video, setelah itu
pilih menu Import pada pada menu Nvivo yang terletak bagian atas jendela, kemudian pilih Ncaptur.
(2) Lalu cari tempat penyimpanan berita online dan atau video yang sudah kita download pada menu Browse, kemudian pilih file berita dan atau vidoe dengan mengklik pada kolom ceklis, selanjutnya klik Import, dan tunggu hingga proses import selesai.
512 | New Normal, Kajian Multidisiplin
(3) Namun untuk file video kita perlu melakukan Transcribe video terlebih dahulu dengan cara klik kiri dua kali file video kita.
(4) Selanjutnya Click to Edit.
(5) Lalu klik menu Synchronize dan klik Transcribe pada menu pilihan yang ada diatas.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 513
(6) Selanjutnya klik play dan ketikkan audio yang terdengar dalam bentuk kalimat pada kolom content yang ada disebelah kanan sampai dengan video selesai. Pada menu Timesplan akan keluar durasi waktu putar video. Setelah Transcribe video selesai maka data siap dianalisis.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari seberapa banyak kata
merdeka yang tertuang dalam data yang berupa teks penelitian. Maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara :
1. Klik menu Exsplore pada jendela menu NVIVO yang terletak diatas.
Selanjutnya klik Text Search.
Synchronize
Transcribe
514 | New Normal, Kajian Multidisiplin
2. Lalu diketik kata “merdeka” pada kolom Search For, kemudian klik
Run Query tunggu hingga proses searching selesai.
3. Setelah selesai maka hasil pencarian disajikan dalam 5 bentuk yaitu Summary, Reference, Text, PDF, dan Word Tree.
4. Dalam hal ini peneliti menggunakan Word Tree, maka untuk menampilkan hasilnya klik Word Tree, selanjutnya klik kanan pilih Export Word Tree.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 515
5. Lalu cari tempat penyimpanan, kemudian klik save. Data hasil analisis siap untuk dibahas.
Pembahasan
Hentakan kata “merdeka” pemberdaya masyarakat di masa pandemi Covid 19 sudah terasa sejak awal Maret 2020, dan sangat terasa karena surat edaran Rektor (SE) UNIB berdampak pada tatanan baru
516 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bidang akademik berkembang di Universitas Bengkulu. SE ini memerdekakan tatanan kehidupan kampus yang sudah nyaman selama berabad-abad menjadi porak poranda karena dosen, mahasiswa dan karyawan harus bekerja dari rumah. Kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka dan sedikit sedikit blended-learning menjadi benar-benar tatap maya. Pengamatan awal yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa sekitar 40% dosen sudah siap melak-sanakan kegiatan tersebut, namun sisanya masih gaptek, atau malah ada yang berlebihan menggunakan Zoom. Akibatnya kuota membengkak.
Hentakkan kata merdeka ini benar-benar memberdayakan masyarakat dengan sangat cerdas, kreatif, kritis dan sangat mandiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut menimbulkan tatanan, kebiasaan dan budaya baru karena masyarakat yang berkerja dari rumah (BDR/WFH). Bekerja dengan berdaster ria, kadang ada kelucuan yang tidak terkendali. Bagian atas rapi tetapi bagian bawah menggunakan celana pendek [16]. Kesempatan untuk lebih mandiri bekerja di rumah dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tanggan dengan mengandalkan tetangga menjadi model berkehidupan baru.
Misalnya pemberdayaan bidang pencegahan penyakit menular Covarius 2019, diperoleh dengan cara menerjemahkan dan menerapkan penggunaan istilah social distance untuk menerapkan hindari kerumunan, tidak perlu berjabat tangan, menjaga jarak fisik agar tidak bersentuhan. WFH (work from home) dengan tujuan melakukan aktivitas bekerja dan belajar dari rumah untuk memutus mata rantai penularan virus. Hand sanitisier = penyitasi tangan dengan tujuan, masyarakat harus hidup bersih. Sering cuci tangan, kalau habis bepergian secepatnya ganti baju dan mandi, keluar rumah menggunakan masker. Fenomena tersebut dapat diterjemahkan bahwa ada perubahan konsep yang secara merdeka dilakukan oleh para pengambil keputusan perikehidupan bangsa. Perubahan konsep yang dimaksud adalah perubahan konsep dari pemahaman manusia yang dulunya adalah mahluk social yang sangat mempunyai kebutuhan khusus dan bergantung kepada sesame, namun saat ini diperkirakan akan bergeser pelan-pelan menjadi mahluk individu yang harus bisa bertahan dengan kompetensi dan kecakapan yang dimilikinya.
Contoh yang lain adalah, tatanan baru pemberdayaan kesehatan, misalnya gak perlu ke dokter jika tidak benar-benar diperlukan karena ada Google Chrom yang menyediakan layanan tersebut. Baca dan konsultasi gratis ke Goegle Chrom membuahkan berbagai penyakit
New Normal, Kajian Multidisiplin | 517
ringan dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut. Ada perubahan yang sangat signifikan pada peri kehidupan bangsa saat pandemic ini, semua permasalahan kehidupan dapat diselesaikan dengan cara membaca. Ya membaca, membaca berbagai sumber permasalahan dengan mengetik kata kunci di berbagai situs. Sehingga teks dan naskah menjadi sumber bacaan dan solusi kehidupan. Guna memperkuat dugaan tersebut dapat kita telusuri hentakan kata merdeka ini di berbagai teks yang berupa SE dan teks-teks lain. Hal ini tampak pada gambar hasil kajian yang digunakan dengan aplikasi NVIVO sebagai berikut. Tabel 1: Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada surat edaran
Data Jumlah Teks Keterangan
Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020
147 0,72%
Kampus-Merdeka 18 0,24% Panduan-Inovasi-Pembelajaran-Digital-1
17 0,19%
Panduan-Program-Bantuan-Program-Studi-Menjadi-Model-CoE-MBKM
90 1,18%
Berdasarkan tabel 1 tampak bahwa kata merdeka benar-benar menghentak dan memberdayakan masyarakat. Sekitar 272 teks ditemukan yang menggunakan hentakan kata merdeka selama pandemic (Maret 2020 sampai Juni 2020). Dapat dibayangkan bahwa hanya sekitar 4 bulan sudah tercipta 272 teks dengan hentakan kata merdeka sekitar 2,33 % pada pemberdayaan kehidupan berbangsa dan berengara di Indonesia. Fenomena ini sangat berbeda secara signifikan dengan kehi-dupan berbangsa dan bernegara tahun tahun sebelumnya yang mungkin hanya 0,01 % saja dan hentakan kata merdeka hanya di bulan Agustus saja. Pembanding data tersebut pada table 1 dapat dibaca gambar 1 berikut.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 519
Gambar 1: Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada surat edaran Berdasar gambaran yang ada di gambar 1 tampak bahwa diagram pohon yang dibentuk oleh kata merdeka demikian komplek berpengaruh pada perikehidupan bangsa ini, sehingga fenomena penggunaan kata merdeka demikian menghentak kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya fenomena hentakan kata merdeka ini dapat kita kaji dari kehidupan dunia maya.
Contoh pemberdayaan yang lain di masa ini adalah uji kecerdasan dan uji kreativitas untuk melaksanakan berbagai panduan yang dikreasi oleh pemerintah. Tujuan pemahaman dan penerapan secara cerdas oleh masyarakat ini adalah agar masyarakat dapat hidup tenang mematuhi bergai panduan. Contoh panduan pemilihan masker, panduan penetapan gizi untuk balita, anak dan kel selama WFH, panduan pembelajaran daring selama WFH untuk siswa dan mahasiswa. Panduan menerima rasmi (beras dan Mie), panduan menerima BLT dan SEMBAKO untuk masyarakat, panduan melaksanakan sholat jamaah di masjid untuk sholat fardhu dan jumat, panduan ke bank (ATM), panduan ke Puskesmas, panduan untuk mengikuti suatu WEBINAR, dan yang terakhir di bulan Mei 2020 ini adalah panduan yang berupa SE dari MUI. Panduan tersebut merupakan panduan untuk melaksanakan sholat idulfitri di rumah untuk masyarakat yang daerahnya masih banyak orang yang terpapar virus corona 2019. Panduan tersebut berupa Surat Edaran MUI No. 28/2020 tentang ibadah idul fitri (tertulis dan suara dalam bentuk video). Panduan ini adalah panduan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah (dua rakaat). Panduan ini berisi peraturan dan tatacara melaksanakan sholat idulfitri di rumah. Panduan-panduan yang lain adalah panduan mudik dengan berbagai syarat protokol kesehatan, dan panduan melaksanakan PSBB.
Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat (yang nota bene adalah mahluk sosial) mulai Maret 2020 dipersiapkan untuk bisa hidup mandiri, agar bisa hidup lebih sehat dan memacu ketertinggalan dengan masyarakat global yang lain, sehingga bisa diprediksi bahwa akan ada perubahan budaya dari mahluk sosial ke mahluk yang lebih mandiri dan individual dengan mengandalkan teknologi. Ayo berubah kalau gak berubah bisa ambyar seperti dinosaurus yang punah ketika tidak mau berubah. Perubahan-perubahan tersebut tampak dalam berbagai berita on-line. Berdasarkan referensi dari sumber ini tampak bahwa hentakan kata merdeka guna memberdaya masyarakat sangat signifikan
520 | New Normal, Kajian Multidisiplin
berpengaruh. Hal ini tampak dari paparan kata merdeka dari media daring (on-line) yang bisa kita lihat paparannya pada tabel 2.
Berdasarkan paparan yang menggunakan refernsi dari berita daring tampak bahwa hentakan kata merdeka untuk memberdaya masyarakat berasal dari satu sumber, yakni pemerintah. Ada sekitar 78 panduan yang khusus mengatur suatu program di salah satu devisi pemerintahan saat pandemic. Berdasar pemahaman konseptual dari berita yang dibaca dalam table 2, tampak bahwa panduan ini dibuat oleh suatu kementrian, yakni kementrian pendidikan atau kementrian ristek dikti. Hentakan kata merdeka guna memberdaya kehidupan pendidikan di tanah air ini tampaknya merupakan suatu program. Program besar yang tiada tandingannya, karena satu-satunya program dari Kementrian Pendidikan untuk periode 2020-2024 hanya beriksar pada upaya memerdekan anak-anak Indonesia melalui pemberdaya Kampus Merdeka [17]. Dengan hentakan kata merdeka yang merupaka sebuah program, ada upaya untuk mendesain ulang kurikulum Perguruan Tinggi agar lebih membumi dan bermakna bagi kehidupan bangsa guna mempersiapkan mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang siap bekerja begitu lulus dari Perguruan Tinggi ini. Hal ini terjadi karena pengaruh pandemic yang telah meluluh lantakkan semua kehidupan bangsa, bahkan fakta selama pandemic berlangsung krisis social mengiringi krisis kesehatan publik. Artinya kehidupan social masyarakat menjadi berbeda.
Krisis multifaser telah meluluh lantakkan pula dunia pendidikan [18]. Krisis ini berpengaruh pada kehidupan Guru dan siswa. Mereka tidak lagi berinteraksi secara tatap muka, namun mereka bertemu dan bertatap maya di dunia daring. Kondisi ini sangat riskan karena anak-anak rindu belaian guru dan senda gurau bersama teman-teman di halaman sekolah. Belaian guru hanya tertuang melalui akses informasi yang ditentukan oleh internet. Anak dibiasakan dengan fenomena belajar dari rumah dan ibu benar benar berperan membimbing dan mendidik anak-anaknya. Guru sebagai penggerak kegiatan belajar yang mmfasilitasi kehidupan belajar anak sehingga kuota menjadi andalan, walaupun digunakan WIFI di rumah, namun kuota masih berperan dalam kehidupan daring mendaring di saat pandemic.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 521
Hasil analisis berita online Tabel Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada berita online
Data Referensi Keterangan
4 Poin Kebijakan 'Kampus Merdeka' Menteri Nadiem Makarim
4 0,50%
Bela Negara di Kampus Merdeka Pada Dunia Baru Pasca Pandemi COVID-19 – Dikti Official Site
5 0,44%
Belajar Merdeka dan Merdeka Belajar di Tengah Corona ~ Harian Bhirawa Online
35 1,84%
Kampus (Merdeka) Era Pandemi Halaman all - Kompasiana.com
4 0,17%
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia
10 0,69%
Kini Mendikbud Telurkan Kebijakan 'Kampus Merdeka', Ada 4 Poin Penting – Siedoo
8 0,58%
Pandemi Covid-19 Momentum Adaptasi Pendidikan Era i4.0 ~ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1 0,16%
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ~ Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran Nomor 1~2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
3 0,24%
Virus Corona dan Pembuktian Kampus Merdeka ~ Republika Online
8 0,49%
Keterbatasan sinyal akan digantikan dengan berbagai upaya
kegiatan belajar melalui TVRI, maupun RRI, bahkan akan dikirim mahasiswa semester 5 yang siap mejadi asisten guru di desanya guna mengajar anak-anak SD dan SMP [19]. Mahasiswa yang melakukan kegiatan ini akan diakui sebagai kegiatan yang mempunyai kredit semester dengan bimbingan dosen, deprogram secara terstruktur dalam KRS, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dosen, sehingga mahasiswa tersebut benar-benar menjalankan program dalam waktu satu semester dengan hitungan dalam SKS. Perbedaannya, mahasiswa
522 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tersebut akan mendapat uang saku dari dirjen dikti. Besarannya lumayan, guna menciptakan roda perekonomian di pasca pandemic.
Hentakan kata merdeka lebih lanjut tampak di dalam kegiatan inovasi dan kreativitas masyarakat. Kondisi ini didukung oleh suatu fakta, bahwa Kementerian Pendidikan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar seolah mendapat kesempatan mewujud-kan cita citanya memerdekakan sekolah dan kampus. Berdasarkan pada SE no. 36962/MPK.H/HK/2020, kementrian ini merilis dan menyasar Perguruan Tinggi dengan program “Mahasiswa bebas belajar maksimal 3 semester di luar Program Studi”. Program ini bertujuan untuk memberi pengalaman belajar baru bagi mahasiswa, terlibat aktivitas menarik, menantang, bahkan “membahayakan” [20], guna berpikir, berkreasi, berimaginasi dan berekpresi sesuai minatnya. Guna mendapatkan pembanding pembahasan di dalam table 2 dapat kita kaji gambar 2.
Berdasar gambar 2 tersebut dapat dibaca bahwa hentakan kata merdeka telah memberdaya kehidupan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka belajar. Program ini dikenal sebagai program tunggal selama 2020-2024 yang melekat pada setiap gerak kementrian. Kondisi ini secara factual sudah melekat pada kehidupan Perguruan Tinggi khususnya di Prodi Magister, sehingga Program Studi Magister dan Program Doktor tidak tersasar untuk program ini. Namun kehidupan di Program Studi Strata 1 agak berbeda, karena gaya mengajar dosen di S1 dan S2 memang agak berbeda. Kehidupan belajar dan mengajar di program S1 masih sepenuhnya bergantung pada paket belajar yang disediakan oleh institusi, sehingga mahasiswa belum merdeka untuk beraktivitas. Walaupun pada kenyataannya, di program S1 sudah dikenalkan dengan matakuliah keahlian mayor dan minor, namun mahasiswa belum bebas dan merdeka untuk berbuat sesuatu di dalam aktivitas belajarnya, sehingga perlu dibuatkan suatu program agar di pasca pandemic mereka dapat berperan serta secara merdeka untuk memutar roda prekonomian bangsa.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 523
Gambar 2: Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada berita online
524 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Fenomena Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa dan
dosen saling bermigrasi antar bidang ilmu. Pola kemitraan antar prodi, antar fakultas atau antar perguruan tinggi dapat menjadi ruang perjumpaan yang effektif dan produktif untuk mengembangkan kerjasama saling memberdayakan. Sehingga memerlukan aturan yang disepakati bersama dan fasilitas kerjasama yang memerlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan kampus merdeka [21]. Dosen sebagai fasilitator dan teman bagi mahasiswa untuk merdeka belajar dan bertualang di kampus merdeka, secara ideal merupakan prasarana bagi dosen untuk membangun kepakaran dan meningkatkan kualitas penelitian serta pengabdian guna memperkuat kepakarannya [22]. Bagi Perguruan Tinggi idealnya ada aturan yang memfasilitasi migrasi belajar, akan memberdayakan mahasiswa menyebarkan, men-transformasi dan menerapkan visi dan misi universitas, serta profesio-nalitas mahasiswa. Bagi pihak swasta (perusahaan dan sekolah), fasilitas migrasi belajar mahasiswa dapat melalui praktik kerja dan magang, seharusnya menjadi kesempatan berinvasi dibidang SDM, mentransfor-masi nilai dan praktik baik yang dimiliki. Realisasi pemikiran ini untuk Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk dapat Merdeka Berbahasa dan Bersastra Untuk Merdeka Belajar [23]. Hentakan kata merdeka ini tidak akan lengkap jika tidak diikuti dengan kajian kata merdeka yang berasal dari youtube. Informasi yang berasal youtube tampak sangat sudah merajai dunia informasi di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan maraknya kehidupan penyebaran informasi yang dilakukan dari youtube. Banyak sekali kanal-kanal informasi yang telah merajai kehidupan bermasyarakat yang berasal dari youtube, baik untuk kegiatan menghibur, memberikan edukasi maupun kegiatan kehidupan keseharian [24]. Berdasar pada fenomena tersebut, dunia maya lebih bervariasi sumber informasinya, begitupun juga yang terjadi pada hentakan kata merdeka dengan mengacu pada kanal-kanal youtube berbagai sumber.
Berdasar pada acuan atau refernsi dari 25 sumber kanal youtube dapat dijelaskan, bahwa hentakan kata merdeka berpengaruh sekitar 3, 04 % pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tampaknya dari penjelasan yang ada pada table 3, kehidupan kampus merdeka dan merdeka belajar disosialisasikan oleh Kementrian Pendidikan dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 525
Kebudayaan melalui kanal ini. Sebagai pembanding dapat kita lihat paparannya pada gambar 3 Tabel 3: Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada video Youtube
Data Referensi Keterangan
Diskusi KAMPUSMERDEKA Hak Belajar Di Luar Prodi.Mp4
4 0,16%
Mahasiswa Setuju Kebijakan Kampus Merdeka.Mp4
6 1,06%
Merdeka Belajar Ala Nadiem Makarim.Mp4 1 0,10% Salah Kaprah Kampus Merdeka Ala Nadiem Makarim Opini Tempo.Mp4
6 0,86%
Siapkah Ub Dengan Kebijakan Kampus Merdeka.Mp4
8 0,86%
Berdasarkan pada paparan yang tampak pada gambar 4 dapat dijelaskan bahwa hentakan kata merdeka secara jelas dapat dibaca dalam diagram pohon tersebut. Misalnya gambaran kampus merdeka dengan berbagai kebijakan yang telah deprogram oleh Kemntrian Pendidikan Dan Kebudayaan. Program tersebut diluncurkan oleh Mentri Nadiem Makariem, dan telah diujicobakan di kampus Universitas Brawijaya. Sementara di sayap kiri dijelaskan tentang kajian kata merdeka ini dengan adanya merdeka belajar yang dimaksudkan oleh mentri Nadiem Makarim di dalam memberdaya semua elemen yang ada di jajaran Kementrian Pendidikan dan Kebudyaan. Salah satu wujud hentakan kata merdeka terjadi pada model komunikasi konvensional. Model komunikasi tersebut adalah seminar dalam daringan, atau webinar. Salah wujud dari ke-merdeka-an yang lain sebagai wujud silahturahmi keilmuan antar pakar dari berbagai perguruan tinggi, antar komunitas, individu dan sejalur di bidang keilmuan, informasi guna berbagi informasi untuk mencerdaskan dan perbaiki kinerja dan ketaqwaan kepada yang Ilahi. Sehingga pengaruh keilmuan yang bersifat multidisipliner menjadi sangat kental. Namun sisi yang sangat disesalkan adalah ketiadaan kegiatan bermain, sehingga media digital yang ada saat ini cenderung meninggalkan sifat-sifat mahluk homo sapiens. Penggunaam media digital cenderung sangat kaku, robotic dan tidak ada unsur bermain [25]
526 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Gambar 4: Hasil analisis Text Search Query - Results Preview kata merdeka pada video Youtube
Penutup
Hentakan kata merdeka di masa pandemi corona virus 19 di Indonesia telah mengubah tatanan masyarakat, dari mahluk sosial ke mahluk individual dan mandiri. Perubahan tersebut sangat dikondisikan oleh pemerintah dengan menghabiskan dana trilyunan rupiah. Berbagai perubahan ini dipandu oleh berbagai macam panduan dan imbauan yang tiada henti. Media yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari Surat Edaran, berbagai media on-line (RRI, TVRI), maupun media social seperti Instagram dan telegram. Media kanal youtube dipergunakan juga sebagai media untuk mempopulerkan kata merdeka guna menghentak kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia guna mengatasi berbagai krisis pada saat pandemic maupun pasca pandemic. Oleh karena itu berimplikasi pada perikehidupan dengan tatanan yang secara signifikan berbeda pada saat sebelum pandemic. Manusia di Indonesia pada khususnya sudah dibiasakan dengan kehidupan sedaring, webinar
New Normal, Kajian Multidisiplin | 527
dan sederet program dengan henatakan kata merdeka, terutama di dunia pendidikan. Kata merdeka menjadi sesuatu yang sacral dan perlu dicermati lebih teliti agar tidak disalah gunakan lebih lanjut. Maknanya hentakan kata merdeka telah memberdaya masyarakat di masa pandemi dengan tujuan memutus rantai penularan virus corona 2019, dan mengubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih mandiri, cerdas, dan kretif serta inovatif di masa pasca pandemi.
Rujukan
[1] Google, "New Normal," Google, 2020.
[2] J. Widodo, "Covid 19," Radio Republik Indonesia, Jakarta, Mei, 2020.
[3] Ambarwati, "Multikrisis," Goegle, 2020.
[4] R. Nuraji, "Peraturan Rektor Universitas Bengkulu," -, Bengkulu, 2020.
[5] R. Nuraji, "Surat Edaran Rektor," -, Bengkulu, 2020.
[6] D. E. C. Wardhana, "Penggunaan IT Mengajar Guru," -, 2020.
[7] N. Sumber, "Seminar Daring Masa Pandemi Covid 19," Universitas Mochammadyah Malang, Malang, 2020.
[8] R. P. Jakarta, "Pembelajaran Untuk SD, SMP dan SMA," RRI Pusat Jakarta, Jakarta, 2020.
[9] HISIKOM, "Webinar," HISIKOM WA Group, Malang, 2020.
[10] G. T. Covid, "Pesan dari Gugus Tugas Covid," Telkom, Bengkulu, 2020.
[11] K. Y. UGM, "PSBB," - , Jogyakarta, 2020.
[12] S. K. Miharjo, Sosiolinguistik, Malang: UM Press, 1990.
[13] A. Bangkit, Writer, Transkripsi dengan Aplikasi. [Performance]. Andy Bangkit Produktion, 2020.
[14] Goegle, "APLIKASI NVIVO," Goegle, -, 2020.
[15] Goegle, "NVIVO," Goegle, -, 2020.
[16] S. Pos, "Zoom Merdeka," Solo Pos, Solo, 2020.
[17] IKAPROGSI, "Workshop Kurikulum," -, Jakarta, 22 Agustus 2020.
[18] Ambarwati, "Krisis Multifraser," Goegle, -, 2020.
528 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[19] Paris, "Kebijakan Kampus Merdeka," Sekjen Dikti Kemendikbud, Jakarta, 2020.
[20] D. Sarnyono, "Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar," Universitas Islam Malang, Malang, 2020.
[21] D. S. Rofiuddin, Multidipliner Dalam Kehidupan Kampus, Malang: UM Press, 2017.
[22] Tempo, "Kampus dan Kepakaran Civitas Akademika," Tempo, Jakarta, 2020.
[23] D. Sarnyono, "Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Bidang Kebahasaan dan Kesasteraan," Universitas Islam Malang, Malang, 2020.
[24] Goegle, "Youtube dan Manfaatnya," Goegle, -, 2020.
[25] D. Sarnyono, "Sedaring dalam Niti Sastra Universitas Negeri Malang," Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Malang, 2020.
[26] J. Widodo, "Pandemi Covid 2019," Jakarta, 2020.
[27] K. Y. UGM, "PSBB," -, Jogya, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 529
Bab 33
Strategi Bertahan Pedagang Pasar di Masa Pandemi Covid 19 Endang Sungkawati38
Pengantar
Saat ini seluruh dunia telah dihebohkan oleh suatu penyakit menular yang disebut covid-19. Pandemi Cocid-19 yang datang tanpa diundang dan sangat tiba-tiba, dan membuat kepanikan di seluruh masyarakat. Dampak dari covid-19 ini mengakibatkan terganggunya kegiatan perekonomian suatu Negara yang dapat menjadi perma-salahan yang sangat fatal (krisis moneter). Dilihat dari sisi perdagangan, adanya pandemi covid 19, menyebabkan segala bentuk aktivitass ekonomi dibatasi, sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah menjadi tidak bisa produktif lagi, banyak konsumen enggan untuk keluar rumah bahkan untuk pergi ke pasar. Bagi produsen, dampak Covid-19 pada saat ini mulai terasa dengan mulai berkurangnya produksi karena menurunnya jumlah permintaan konsumen dan dibatasinya aktivitas perdagangan. Dan bagi pedagang menurunnya jumlah pembelian sangat terasa dengan ditutupnya akses untuk berjualan maupun ketakutannya masyarakat untuk keluar rumah apalagi dengan berbelanja ke pasar.
Covid-19 sangat berdampak pada unit-unit usaha kecil, salah satunya para pedagang di pasar tradisional. Jumlah pedagang di pasar tradisional diperkirakan dapat menurun sebesar 29%, sementara omzet rata-rata pedagang menurun sebesar 39% [1]. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Karangploso dan Singosari Malang, dampak dari Covid-19 ini menyebabkan pedagang pasar kehilangan pembelinya. Suasana pasar menjadi sepi, bahkan banyak bedak-bedak (lapak) yang tutup. Gambar berikut menunjukkan suasana pasar yang sepi, akibat adanya pandemi Covid-19.
Gambar 1. menunjukkan penjual sayur yang sedang menunggu dagangannya dan menunggu pembeli. Tampak bahwa masih banyak dagangannya yang belum terjual dan masih menumpuk akibat berkurangnya pembeli. Pasar Karangploso maupun pasar Singosari merupakan pusat pedagang sayur dan buah, di mana para pedagang
38 Dr. Endang Sungkawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana
Malang
530 | New Normal, Kajian Multidisiplin
menjual hasil pertanian dan menjual secara grosir maupun eceran. Menurut pedagang sayur, hal tersebut sudah terjadi setiap hari semenjak adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya lock down maupun social distancing.
Gambar 1. Pedagang Sayur Sebelum adanya pandemi, setiap hari dagangannya habis karena
yang membeli kebanyakan adalah penjual sayur keliling (mlijo). Bahkan mereka berjualan tidak sampai siang, biasanya jam 09.00 WIB mereka sudah tutup lapak karena dagangannya sudah habis. Akan tetapi, dengan adanya pandemi, setiap hari sayuran menumpuk, menunggu sampai jam 12.00 tidak semua langganan (mlijo) yang datang, penjualan menurun, sehingga ini pada akhirnya menimbulkan kerugian yang disebabkan banyak sayur yang membusuk dan tidak bisa dijual. Demikian juga dengan pedagang yang ada di pasar tradisional lainnya.
Pada gambar 2 memperlihatkan suasana blok lapak penjual pakaian dan blok penjualan sembako. Kedua blok tersebut juga menampakkan suasana yang sepi, lengang bahkan kelihatan bersih. Sama seperti yang dikeluhkan pedagang sayuran, pada kedua blok tersebut mengalami sepi pembeli. Khusus untuk penjual pakaian, menyatakan bahwa dalam satu hari belum tentu ada yang mampir ke lapaknya, apalagi yang membeli. Pada saat hari raya Idul Fitri (lebaran) biasanya dagangannya banyak yang terjual, untuk lebaran kali ini sepi
New Normal, Kajian Multidisiplin | 531
bahkan justru merugi. Pada penjual sembako, pada saat terjadinya pandemic Covid-19 benar-benar merasakan kerugian yang besar. Modal usahanya berhenti pada dagangan, mereka tidak bisa lagi kulakan. Sama seperti penjual pakaian maupun pedagang sayuran, mereka merasakan dampak yang cukup signifikan.
Gambar 2. Pedagang Pakaian dan Sembako Para pedagang sayuran, penjual pakaian, penjual kebutuhan
pokok, masih optimis bahwa pandemi yang terjadi pasti ada akhirnya. Mereka masih bertahan berjualan meskipun sepia tau tidak ada pembeli. Mereka berharap masih ada pembeli yang berani untuk ke pasar. Ketika para pedagang di pasar tradisional memiliki nasib yang sama, mereka semakin solid dan semakin dekat satu sama lain. Mereka menghilang-kan persaingan, yang ada ada interaksi sosial yang semakin baik. Banyaknya pedagang di pasar tradisional yang menjual secara grosir maupun eceran tentunya akan menciptakan suatu interaksi sosial maupun hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya diantara para pedagang yang sejenis. Menurut pengamatan, interaksi sosial yang terjadi pada pedagang sayuran, penjual pakaian maupun penjualan kebutuhan pokok di pasar tersebut adalah interaksi sosial antara pedagang dengan konsumen, pedagang dengan pemasok, serta sesama pedagang barang yang sejenis. Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok manusia [2], yang mana hasil dari proses interaksi sosial di pasar tradisional ini berakibat pada ekonominya, yakni mendapatkan keuntungan berda-
532 | New Normal, Kajian Multidisiplin
gang, dan peningkatan omzet jualnya.
Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan konsumen adalah adanya kesepakatan dan transaksi jual beli. Hal ini mengenai interaksi saat melakukan proses tawar-menawar harga yang berakhir dengan gagal atau tidaknya dalam jual beli tersebut. Pada saat merebaknya pandemi covid-19, interaksi di pasar tidak terjadi seperti yang seharusnya. Interaksi tersebut terhenti khususnya interaksi antara pedagang dengan pembeli. Sesuai pengamatan di lapangan, interaksi antara penjual dan pembeli tidak terjadi karena adanya keterbatasan komunikasi, di mana diberlakukan social distancing, lock down, serta adanya himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Apalagi dengan santernya berita tentang cepatnya wabah ini menular pada orang lain, di berlakukannya social distancing menyebabkan masyarakat enggan untuk berbelanja di pasar.
Interaksi sosial juga terjadi antar sesama pedagang. Interaksi sosial yang terjadi antar pedagang mengakibatkan satu dengan yang lain dapat memberi pengaruh dalam bersikap dan berperilaku dalam kegiatan ekonomi. Interaksi sosial tersebut menghasilkan hubungan kerja [1], [3], [4]. Hubungan kerja antar pedagang di pasar tradisional lebih didominasi oleh hubungan yang bersifat kerjasama, walaupun kenyataannya ada juga hubungan yang bersifat persaingan. Menurut persepsi pedagang, bahwa iklim persaingan di luar pasar lebih tajam dan sementara di pasar trdisional walaupun terdapat persaingan masih terdapat iklim kerjasamadan keharmonisan serta tolong menolong [5], [6].
Menunjuk realitas yang terjadi pada pedagang sayuran, penjual pakaian, dan penjual kebutuhan pokok, bentuk kerjasama yang dilakukan antar sesama pedagang adalah dalam hal bertukar informasi [7], [8]. Disini terlihat ketika seorang pedagang (misal pedagang sayuran dan buah ) menuju ke bedak pedagang sayuran dan buah lainnya untuk menanyakan sayur atau buah yang tidak terjual, pedagang lainnya bersedia untuk membantu menjualkannya. Bahkan mereka melakukan tukar menukar barang, agar barang dagangan sesama pedagang laku terjual, bahkan jika bisa tidak ada sisa atau bahkan busuk. Interaksi antar pedagang ini semakin kelihatan pada saat terjadinya pandemic covid-19, sesama pedagang kelihatan sekali rasa sosial diantara sesama pedagang dan saling membantu. Bentuk hubungan kerjasama lainnya adalah pinjam-meminjam, yang merupakan kebiasaan yang dijalani
New Normal, Kajian Multidisiplin | 533
oleh para pedagang di pasar sebagai wujud adanya hubungan timbal balik yang memberikan nilai keefektifan dan keefisienan serta saling menguntungkan antar sesama pedagang di pasar [9], [4], [3]. Kerjasama lain yang terjalin antar sesama pedagang sayuran dan buah di pasar tradisional adalah dalam hal menyamakan harga jual dengan membuat sebuah kesepakatan harga untuk barang-barang tertentu dari satu agen pemasok. Hal ini disepakati bersama antar sesama pedagang dengan tujuan agar tidak menimbulkan pertikaian dan perselisihan [1].
Berdasarkan uraian atas kenyataan yang diperoleh mengenai bentuk interaksi sosial antara pedagang dengan konsumen, interaksi sosial pedagang dengan pemasok, dan interaksi sesama pedagang di masa tercadinya pandemic covid-19 ini, maka tergugahlah untuk melakukan pengamatan lebih dalam lagi untuk menjawab atas pertanyaan; “bagaimana interaksi sosial pedagang di pasar tradisional dalam upaya bertahan di masa pandemi Covid-19” Tujuan dari pengamatan ini adalah : 1) Memahami dan mendapatkan temuan baru mengenai interaksi sosial antara pedagang dengan konsumen dalam upaya bertahan di masa pandemi Covid-19, 2) Memahami dan mendapatkan temuan baru mengenai interaksi sosial antar sesama pedagang di masa pandemi Covid-19 dalam upaya bertahan berdagang di pasar. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah untuk dilakukan observasi. Oleh karena itu, maka ditetapkan lokasi pengamatan di pasar Karangploso dan pasar Singosari Kabupaten Malang. Pemilihan 2 pasar tersebut sebagai tempat pengamatan, karena ke dua pasar merupakan tempat bertemunya para pedagang yang menjual sayur dan buah yang dihasilkan oleh petani di daerah Malang dan Batu, tempat kulakan bagi pedagang eceran dan merupakan tempat pedagang sayur dari luar kota maupun pedagang sayur keliling untuk kulakan. Jika waktu pagi konsumenpun banyak yang membeli sayur dan buah di ke dua pasar ini karena menganggap harganya lebih murah (harga kulakan).
Pembahasan
Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan- hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perseorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok-kelompok manusia [10], [2]. Interaksi sosial adalah proses dimana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan [2]. Interaksi sosial
534 | New Normal, Kajian Multidisiplin
adalah satu proses, melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang lain, ia adalah suatu proses timbal balik dengan mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain dan dengan berbuat demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain (Roucek dan Warren, dalam [10]).
Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia [2], [5]. Dalam interaksi juga terdapat simbol, dimana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara dua orang atau lebih baik individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dimana perilaku atau kelakuan yang satu dapat mem-pengaruhi dan mengubah perilaku atau kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di Pasar tradisional di Kabupaten Malang bahwa interaksi sosial dilakukan oleh pedagang dengan sesama pedagang, pedagang dengan konsumen, serta pedagang dengan pemasok barang.
Syarat utama terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi, dimana kedua hal tersebut harus terpenuhi ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain[11][12]. Seperti halnya fenome-na yang terjadi di pasar, antar pelaku pasar yakni pedagang, pemasok, dan konsumen saling berinteraksi satu sama lain. Tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi tersebut orang tidak dapat melakukan percakapan dan perilaku sosial tidak dapat terbentuk jika orang tidak melakukan interaksi sosial dengan seseorang, baik interaksi yang secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial di pasar terjadi karena didorong oleh sejumlah faktor, baik yang ada pada diri seseorang maupun ada pada orang lain atau pada lingkungan sekitar. Hasil pengamatan didapati bahwa bentuk interaksi sosial pedagang di pasar dalam upaya bertahan untuk berdagang di pasar, yaitu interaksi sosial yang dilakukan antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen, peda-gang dengan pemasok.
Hubungan Pedagang dengan Pedagang
Hubungan baik antar pedagang dengan pedagang yang terjalin menunjukkan bahwa kepercayaan juga memiliki andil sehingga
New Normal, Kajian Multidisiplin | 535
hubungan kerjasama yang terjalin diantara mereka begitu baik. Mereka kemudian tidak segan untuk sekedar bertukar informasi dengan pedagang yang lain [11]. Baik itu informasi tentang tempat berjualan maupun informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Tidak hanya sampai disitu, hubungan baik ini juga berlanjut pada kehidupan pribadi para pedagang antara lain ketika punya hajat akan saling mengundang untuk hadir begitu juga apabila ada yang meninggal maka mereka juga akan melayat. Bentuk komunikasi yang dilakukan antara pedagang dengan sesama pedagang adalah dalam hal kerjasama dan persaingan[1], [3], [9]. Persaingan dalam mendapatkan kunjungan pembeli dan terjadi perang harga produk yang sama diantara pedagang. Ketika terjadi perang harga produk yang sama, maka untuk menghindari adanya konflik atau perselisihan antar pedagang, dengan modal sosial yang sudah mereka miliki sebelumnya justru tetap terjalin hubungan kerjasama diantara mereka. Kerjasama dalam hal jual beli barang dan menyamakan harga jual barang yang sama. Pada saat seorang pedagang tidak mempunyai suatu jenis barang yang sedang dicari pembeli dibedaknya, maka agar tidak kehilangan pembeli, seorang pedagang berupaya untuk mencarikan barang dimaksud ke pedagang lain yang tersedia stoknya[13][8].
Ketika transaksi jual beli barang antar sesama pedagang ini terjadi, maka hal ini menunjukkan terdapat tukar kebaikan dan saling tolong menolong antar sesama pedagang. Pada saat terjadi kerjasama antar pedagang dalam menyamakan harga jual barang yang sama, maka hal ini diperlukan untuk menjaga hubungan keakraban yang sudah terjalin dengan baik diantara mereka [3][6]. Sebagai makhluk sosial, modal sosial diperlukan diantara sesama pedagang karena sifat manusia adalah saling memerlukan orang lain, dan untuk itu terdapat kecenderungan untuk dapat bekerjasama dan saling berinteraksi termasuk dalam bertransaksi. Untuk menghindari konflik atau perselisihan dan tetap menjaga hu-bungan sosial dan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik, sehingga dalam hal perang harga produk yang sama antar sesama pedagang dibutuhkan suatu kemunculan ide kreatif baru, inovasi produk yang berbeda dari pedagang itu sendiri, sehingga dengan produk-produk baru dan berbeda tersebut, dengan kualitas yang lebih baik dan menarik, maka dengan ini seorang pedagang dapat meningkatkan harga jual yang lebih kompetitif kepada konsumennya [9], [14], [15]. Selain inovasi produk, inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dibutuhkan seorang pedagang kepada konsumennya, sehingga dengan inovasi-
536 | New Normal, Kajian Multidisiplin
inovasi tersebut akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi, lebih kompetitif, dan berdaya saing, sehingga tujuan dalam meningkatkan omzet penjualan bisa tercapai dengan lebih baik.
Interaksi sosial merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan bersama [16]. Dengan kepercayaan, orang tidak akan mudah curiga yang sering menjadi penghambat dari kesuksesan suatu tujuan. Kepercayaan merupakan modal utama dalam menjalin hubungan dengan individu lain maupun dengan pihak lain. Kepercayaan akan mendorong terwujudnya keharmonisan dalam berhubungan dengan pihak lain yang diwujudkan dalam sikap saling membantu antar pedagang di pasar [2], [5], [11].
Kehidupan pedagang di pasar tradisional membuktikan bahwa kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan dagang sesama mereka, seperti yang diungkapkan oleh Informan, kadangkala harus pergi keluar untuk sholat, dan itu berarti dia harus meninggalkan barang dagangannya. Namun, ketika ditinggal pergi maka pedagang sebelahnya yang akan melayani pembeli sayurnya, tanpa menghitung komisi yang akan di dapatkan dari pedagang lain dan begitu pula sebaliknya. Ketika pedagang kembali, pedagang sebelahnya yang membantu melayani konsumen, tinggal melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan sayurnya selama dagangan tersebut di tinggal oleh pedagang lain. Tidak ada perhitungan komisi, bagi hasil atau apapun dalam hubungan ini, tetapi rasa percaya yang dimunculkan. Masing-masing pedagang percaya, bahwa sesama pedagang harus saling membantu jika ingin barang dagangannya juga ikut laku terjual. Kepercayaan diantara para pedagang ternyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling membantu dan tidak saling curiga. Nilai-nilai kepercayaan yang tertanam pada diri individu pada akhirnya menjadi sarana tersendiri bagi terciptanya hubungan yang harmonis di tengah kehidupan pedagang di pasar yang penuh persaingan dan dekat dengan konflik. Namun, adanya interaksi sosial, komunikasi yang baik, rasa saling percaya yang sangat terjaga membuktikan bahwa ditengah musibah dan wabah pandemi covid-19 sekalipun, masih tersimpan solidaritas yang tinggi diantara pedagang di pasar.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 537
Trust adalah hubungan antar manusia dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satuatau kedua belah pihak. Di dalamnya terdapat elemen yang meliputi kejujuran, keramahan dan saling menghormati. Hal tersebut merupakan beberapa bentuk sikap positif yang ditemukan dalam interaksi sosial sesama pedagang di pasar[10], [16]. Sejalan dengan penelitian terdahulu [1], [7], [8] budaya gotong-royong, tolong menolong, penempatan lapak usaha, aturan membayar retribusi parkir, sampai ketertiban tempat usaha dan waktu berjualan adalah norma-norma yang dibangun ditaati bersama dan menjadi tumbuh dengan baik. Ini mencerminkan norma informal berlanjut kepada timbulnya trust (kepercayaan) diantara pedagang di pasar tradisional. Kerjasama diwarnai oleh hubungan timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh nilai sosial yang positif dan kuat. Oleh karenanya, jaringan sosial menjadi fasilitator dalam mendukung terjadinya interaksi yang kemudian akan menumbuhkan kepercayaan dan kerjasama yang kuat. Semakin kuat jaringan sosial yang terbentuk maka semakin kuat pula kerjasama dan kepercayaan yang ada di dalamnya.
Selain kepercayaan, yang tidak kalah pentingnya bagi sesama pedagang sayur dan buah di pasar adalah adanya keterbukaan. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk saling bercerita tentang masalah yang mereka alami, baik itu masalah perdagangan ataupun masalah pribadi. Kedekatan fisik dalam menjajakan barang dagangan menjadi salah satu faktor pembentukan hubungan tersebut. Seperti yang terlihat di pasar tradisional bahwa lapak-lapak yang digunakan untuk berdagang tidak ada batasan yang mencolok antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Pedagang dapat berkomunikasi secara terbuka, tanpa ada batasan fisik apapun, mereka saling mengobrol setiap harinya dan tanpa disadari dengan kedekatan fisik lapak mereka akan menciptakan rasa kebersamaan antar padagang. Kesamaan yang dimiliki seseorang dengan orang lain telah menjadikan hubungan yang semakin kuat seperti yang terlihat dalam aktivitas ekonomi pedagang di pasar. Setiap pedagang telah memiliki rasa kebersamaan, kebersamaan yang didasari kesamaan nasib mereka, kesamaan profesi, dan kesamaan pemikiran.
Pada dasarnya interaksi sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan
538 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien [16]. Melalui jaringan sosial, individu akan mudah mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang tersedia di lingkungannya untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karenanya, terbentuknya jaringan sosial biasanya dikaitkan dengan persamaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai anggota-anggotanya.
Hubungan Pedagang dengan Konsumen
Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan konsumen adalah dalam transaksi jual beli tawar menawar barang dan harga. Sudah menjadi resiko seorang pedagang di pasar ketika pembeli menawar barang dengan harga yang rendah, menjadi hal yang biasa dirasakan oleh kebanyakan pedagang di pasar. Untuk mendapatkan pembeli sehingga terjadi sukses bertransaksi dan untuk menciptakan serta tetap menjaga sebuah jaringan kepelangganan diperlukan beberapa cara. Salah satu cara yang dilakukan oleh seorang pedagang yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik yang lebih berkualitas setiap ada kunjungan kepada pembeli maupun calon pembeli. Bentuk-bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh pedagang kepada calon pembelinya adalah dengan berkomunikasi yang baik saat proses tawar menawar harga, sehingga hal ini akan dapat menjalin keakraban antara pedagang dengan konsumen, tidak memaksakan calon pembeli saat proses tawar menawar harga, sehingga diperlukan sikap kesabaran yang harus dimiliki seorang pedagang dan memberikan kenyamanan untuk calon pembelinya [13], [8], [17].
Bentuk lain yang harus dilakukan oleh pedagang adalah selalu update informasi mengenai produk-produk baru, model atau jenis barang yang sedang tren, perubahan harga barang, sehingga sebagai seorang pedagang selalu bisa membaca keinginan tren calon pembeli; dalam ketersediaan barang di lapak sendiri pedagang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan calon pembeli dengan mencarikan barang ke lapak pedagang lain yang mempunyai stok persediaan barang yang dimaksud pembeli atau dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan pedagang untuk mencarikan ke agen pemasok sesuai waktu yang ditentukan dalam kesepakatan; selain itu mengganti barang yang rusak dari konsumennya merupakan bentuk pelayanan yang selalu dilakukan oleh seorang pedagang, sehingga pedagang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan konsumennya agar upaya untuk membangun jaringan kepelangganan bisa tercapai[13][18].
Sikap tidak mengecewakan pembeli dilakukan juga dalam mem-
New Normal, Kajian Multidisiplin | 539
berikan informasi yang benar atau symmetric information kepada pembeli mengenai kebenaran informasi kualitas produk dan harga produk yang menginformasikan perihal kelebihan maupun kekurangan dari produk itu sendiri, sehingga sikap kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pedagang kepada pembelinya untuk menghindari suatu kebohongan atau kecurangan dikemudian hari yang merugikan pembeli maupun pedagang itu sendiri, sehingga dengan selalu memberikan informasi yang benar apa adanya dapat menciptakan hubungan kepelangganan yang lebih erat, serta hal ini dapat memberikan keuntungan untuk pedagang dalam mendapat pendapatan dan omzet jual yang semakin meningkat.
Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama [16]. Ada semacam kepercayaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari para pedagang dalam menjalankan aktifitas berdagang mereka. Kepercayaan yang di miliki untuk mempererat kembali kelompok mereka, membuat rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan rasa hubungan keluarga, saling membantu, guna mencapai tujuan bersama dan bersama-sama bisa mendapatkan keuntungan, meski tidak hanya keuntungan yang berupa materi namun juga keuntungan immateri [3], [9], [7], [6],
Hubungan Pedagang dengan Pemasok
Hubungan kerjasama yang terjalin antara pedagang dengan pemasok barang adalah transaksi jual beli barang. Seorang pedagang memulai kegiatan usahanya berawal dari membeli barang ke agen pemasok secara tunai atau cash, maka keinginan agar bisa dilakukan pembelian barang dengan cara ditempo ditempuh oleh seorang pedagang dengan membangun kepercayaan kepada agen pemasok. Ketika kepercayaan ini sudah timbul, maka dengan mudahnya agen pemasok dapat memberikan apa yang dikehendaki oleh pembelinya, dalam hal ini adalah pedagang di pasar tradisional. Dari yang semula transaksi dilakukan secara tunai atau cash, maka dengan kepercayaan yang sudah didapatkan oleh pedagang tersebut akhirnya untuk mendapatkan supply barang dari agen pemasok bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi atau barang ‘nyaur ngamek’.
Bilamana barang ‘ngamek’ tidak laku pada saat harus dipenuhinya ‘nyaur’, maka untuk menjaga reputasi terhadap agen pemasok, maka barang tersebut tidak dikembalikan pada agen
540 | New Normal, Kajian Multidisiplin
pemasok, namun dilunasinya kewajiban pembayarannya [5]. Pola semacam ini merupakan komitmen untuk memelihara kepercayaan dengan agen pemasok. Namun, pada saat adanya pandemi Covid-19 sekarang ini pola tersebut tidak dilakukannya dikarenakan para pedagang mengalami masa yang sepi pembeli dan masih banyaknya barang dagangan yang belum terjual. Mereka tidak mau mengalami keterlambatan waktu pembayaran sehingga akhirnya tidak mendapat-kan kepercayaan lagi dari salah satu agen pemasoknya. Keterlambatan ini terpaksa terjadi dikarenakan pasar sepi pembeli, adanya penurunan omzet. Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu penjual kebutuhan pokok, di merupakan bukti bahwa keterlambatan dalam membayar hutang kepada agen pemasok berakibat yang sangat buruk yaitu kehilangan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemasok. Dari kejadian ini maka para pedagang harus memulai membangun kepercayaan lagi dengan agen pemasok yang lain. Hal ini memberikan bukti bahwa betapa berharganya sebuah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita.
Pada saat kepercayaan itu ada, maka justru agen pemasok tidak segan-segan memberikan sebuah penawaran menyuplai barang kepada pedagang dengan sangat mudah dan gampang. Kemudahan ini dapat terjadi karena sebagai pemasok pun mereka membutuhkan barangnya terjual laku dipasaran terlebih untuk barang yang lama tidak laku ataupun barang macet, dengan tujuan pemasok yang juga ingin menambah dan meningkatkan omzet jualnya serta untuk kelancaran perputaran modal usahanya. Dengan bermodal keper-cayaan yang ada maka oleh keduanya antara pedagang dan pemasok barang dapat saling menguntungkan, saling membantu, terlebih dalam menambah pendapatan sehingga dapat meningkatkan omzet penjualannya.
Pada masa terjadinya pandemi Covid-19, hubungan antara pedagang dengan pemasok tidak dapat berjalan dengan semestinya. Walaupun diantara mereka sudah terjalin kerjasama dan saling percaya, para pedagang tidak berani mengambil resiko. Mereka tidak mau mengambil barang dan membayar kemudian (nyaur ngamek), karena adanya ketidak pastian penjualan barang dagangannya. Kondisi sepinya pembeli di pasar tradisional menyebabkan barang dagangannya tidak dapat terjual, sehingga tidak berani untuk kulakan lagi.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 541
Penutup
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa di masa pandemi Covid-19 terbangun interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan sesama pedagang, pedagang dengan konsumen, pedagang dengan pemasok. Interaksi sosial antar pedagang adalah dalam hal kerjasama jual beli barang dan menyamakan harga jual barang yang sama, sehingga terjadi tukar kebaikan, saling tolong menolong, dan menjaga hubungan keakraban sebagai bentuk adanya social capital. Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan konsumen adalah dalam jual beli tawar menawar barang.
Seorang pedagang harus menciptakan sebuah inovasi pelayanan (service innovation) yang lebih berkualitas kepada konsumennya, yaitu dengan berkomunikasi yang baik, tidak memaksakan pembeli, update informasi barang, ketersediaan barang, mengganti barang yang rusak, dan kebenaran informasi (symmetricinformation), sehingga menciptakan jaringan kepelangganan, hal ini juga sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan omzet penjualan. Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan pemasok barang adalah dalam hal transaksi jual beli barang. Jual beli disini diawali dengan menggunakan sistem tunai atau cash. Kemudian pedagang membangun sebuah kepercayaan kepada pemasok agar bisa menggunakan sistem nyaur ngamek. Ketika sudah dipercaya oleh agen pemasok barang dalam hal supply barang, maka seorang pedagang harus bisa menjaga kepercayaan tersebut dengan baik, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik serta peningkatan omzet jual pun dapat dicapai denganmaksimal.
Bagi pedagang, di masa Pandemi Covid-19 harus bisa menjadi seorang teman yang baik untuk sesama pedagang lainnya, perasaan senasib, seprofesi, sikap saling tolong menolong, meningkatkan kepercayaan, menjaga hubungan keakraban yang sudah terjalin dengan baik, walaupun tetap bersaing tetapi bersaing secara kreatif, sehingga mempunyai daya saing yang lebih kompetitif dan inovatif, membangun proses asosiatif berupa kemampuan akomodatif untuk tujuan bersama.
Rujukan
[1] T. A. Ningrum, “Pola Interaksi Sosial Antar Pedagang Di Wilayah Ampel Surabaya,” J. Kaji. Moral dan Kewarganegaraan, vol. Volume 02, no. Nomor 03, pp. 497–511, 2015.
542 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[2] S. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012. [3] S. Mu’Arofah, “Pola Interaksi Sosial Antar Pedagang Buku Di
Pasar Wilis Kota Malang,” J. Art, Des. Art Educ. Cult. Stud., vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2019.
[4] Merliya and Ikhwan, “Pola Interaksi Sosial Pedagang Dengan Nelayan Di Pasar Ikan Pantai Purus Padang Kecamatan Padang Barat,” J. Perspekt., vol. 2, no. 4, pp. 1–8, 2019.
[5] S. Leksono, Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional. Malang: CV. Citra Malang, 2009.
[6] W. Kristiningtyas, “Eksistensi Pasar Tradisional Ditinjau Dari Konsep Geografi, Interaksi Sosial Dan Perilaku Produsen-Konsumen,” J. Educ. Soc. Stud., vol. 1, no. 2, pp. 139–145, 2012.
[7] Munandar, “Peran Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Miskin Perkotaan Pada Pedagang Sektor Informal di Kota Semarang,” J. FIS, vol. 37, no. 2, pp. 1–11, 2010.
[8] A. P. Panggabean, “Kualitas Interaksi Sosial antara Penjual dan Pembeli di Taman Pintar Book Store Yogyakarta,” Indig. J. Ilm. Psikol., vol. 2, no. 2, pp. 106–118, 2017.
[9] Megawati, “Interaksi Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun Kabupaten Karimun Kepulauan Riau,” JOM FISIP, vol. 4, no. 2, pp. 1–16, 2017.
[10] Abdulsyani, Sosiologi: skematika, teori dan terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
[11] N. Setiyawan, S. Leksono, and E. Sungkawati., “Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Untuk Berjualan di Pasar Besar Malang,” J. Penelit. Pengkaj. Ilm. Mhs., vol. 1, no. 1, p. Universitas Wisnuwardhana Malang, 2020.
[12] S. Leksono and E. Sungkawati., “Can Entrepreneurship Behavior Through Innovation Increase the traditional Market Traders Performance?,” Acad. Entrep. J., vol. 25, no. 3, 2019, [Online]. Available: https://www.abacademies.org/articles/can-entrepreneurship-behavior-through-innovation-increase-the-traditional-market-traders-performance-8523.html.
[13] D. Aryani and F. Rosinta, “Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan,” Bisnis Birokrasi J., vol. 17, no. 2, pp. 114–126, 2010.
[14] D. Cravens, W, Strategi Marketing, Edisi 7. New Tork: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 543
[15] I. Purwanto, Manajemen Strategi. Jakarta: Trama Widya, 2007. [16] F. Fukuyama, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran.
Yogyakarta: Qalam, 2007. [17] P. Kotler and K. L. Keller, Manajemen Pemasaran Terjemahan Bob
Sabran., Edisi Keti. Jakarta: Erlangga, 2009. [18] Setiyawan, “Relationship Marketing dalam Membangun Loyalitas
melalui Kepuasan Pelanggan Paket Data,” Arthavidya, vol. 20, no. 2, pp. 130–140, 2018.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 545
Bab 34
Himmatul ‘Amal Dalam Ekonomi Islam Saat New Normal A. Ifayani Haanurat39
Pengantar
New normal merupakan suatu istilah yang ditujukan pada perilaku manusia yang berubah dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bahasan mengenai new normal begitu mengemuka mulai dari masalah kedokteran, kesehatan masyarakat hingga sosial ekonomi, bahkan new normal dijabarkan sebagai adaptasi dari proses yang hanya sementara selama adanya pandemic Covid-19, artinya manusia akan mempunyai kebiasaan baru dan juga akan beradaptasi dengan proses yang dilaluinya setelah pandemik ini berlalu.[1],[2],[3].
Disisi lain jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, maka new normal disebut sebagai al-ta’ayusy atau hidup berdampingan, artinya selama adanya pandemik ini maka kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19, jadi bukan berdamai, ini didasari oleh alasan dari ahli epidemik corona yang berpendapat, bahwa Covid-19 akan tetap bertahan lama, namun roda perekonomian dituntut harus tetap berjalan untuk menopang kebutuhan masyarakat.[4].
Atas situasi pandemik ini maka pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi masyarakat. Selain itu, agar perekono-mian tetap berjalan, pemerintah juga menghimbau para pelaku usaha dan industri untuk tetap menjalankan usahanya selama pandemik dengan memberlakukan protokol kesehatan lebih ketat. Bahkan perkantoran dan pabrik dihimbau untuk melakukan penyemprotan desinfektan setiap 4 jam sekali, sedangkan bidang usaha yang bersentuhan langsung dengan layanan publik dianjurkan untuk memasang tabir kaca sebagai pembatas antara pekerja yang memberikan pelayanan kepada pelanggan.[5],[6].
Karena itu tidak ada jalan yang dapat di tempuh kecuali dengan hidup berdamping bersama Covid-19 walaupun dalam arti sebenarnya kita tetap bermusuhan.[4],[7]. Dan sebagai masyarakat muslim kita di tuntut untuk komitmen dan istiqomah di semua sektor kehidupan yang menyeluruh (kaffah), termasuk juga dalam manajemen organisasi yang
39 Dr. A. Ifayani Haanurat., MM, Program Studi Magister Manajemen, Universitas
Muhammadiyah Makassar
546 | New Normal, Kajian Multidisiplin
syar’i untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah di canang-kan pemerintah. Namun yang menjadi masalah, masih banyak individu yang bekerja tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan dengan istiqomah yang kaffah, ini terlihat dari pertambahan jumlah penderita Covid-19 yang setiap hari semakin tingginya jumlah. Adapun angka peningkatan kasus positif Covid-19 sampai pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sudah menembus angka 162.884 orang di Indonesia.[8].
Selain itu normal baru atau new normal juga merupakan kondisi atau kebiasaan sosial masyarakat terhadap perilaku setiap individu yang tampak dengan adanya covid-19.[7]. Dalam ekonomi Islam, terbentuknya berbagai kebiasaan yang dipengaruhi oleh budaya ataupun kebiasaan sosial dan sistem nilai yang diyakini, serta pandangan dan kebiasaan kerja yang dijalankan dengan istiqomah atau konsisten untuk membenahi diri menjadi lebih baik, disebut sebagai himmatul ‘amal. [9],[10]. Namun yang menjadi masalah di dalam era new normal ini karena kebiasaan sosial ekonomi ataupun kebiasaan kerja dibentuk oleh latar belakang keyakinan baik budaya maupun agama yang berbeda-beda, sehingga untuk mengaktualisasikan kebiasan kerja dalam kehidupan sehari-hari bukanlah suatu yang mudah dan kompleksitas, karena melibatkan kondisi dan prakondisi yang banyak, seperti fisik, mental psikis, sosio kultural, dan mungkin juga spiritual trasendental, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak saat new normal ini.
Karena itu ekonomi Islam dengan berbagai bentuk dan bagiannya terutama himmatul ‘amal sangat di harapkan dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya terutama pemahaman motivasi diri pada masyarakat maupun individu untuk lebih peduli pada lingkungannya agar menjadi ummat yang lebih baik (khaira ummah). Atas dasar itu maka aspek yang perlu mendapat perhatian untuk di paparkan yakni upaya menerapkan himmatul ‘amal secara kaffah di saat new normal baik bagi prilaku individu itu sendiri maupun lingkup organisasi.
Pembahasan
Ajaran yang di emban dalam ekonomi Islam merupakan satu bagian dari keseluruhan aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan di akhirat (QS. al-Qasas: 27), disamping itu eksistensi manusia akan memiliki makna jika keseluruhan aktivitas hidupnya didedikasikan kepada Allah SWT sebagaimana yang ada dalam firman Allah dalam QS. an-Nahl: 97, ayat ini menunjukkan, bahwa siapapun yang beramal saleh dan beriman,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 547
apakah pria atau wanita walaupun tidak mempunyai harta akan di berikan penghidupan yang baik dan diberikan pahala melebihi dari yang dikerjakannya di dunia.
Bagian dari aktivitas ibadah dan bekerja dengan sungguh-sunggguh serta dorongan atau motivasi karena melaksanakan perintah Allah SWT dengan menyeluruh atau kaffah, dalam ajaran serta pandangan Islam disebut dengan himmatul ‘amal. Bekerja dengan sungguh-sungguh merupakan salah satu penghapus dosa, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam HR. Ahmad dan HR. Thabrani. [11].
Dalam ekonomi Islam himmatul ‘amal dikenal dengan istilah etos kerja Islam, yang juga merupakan penggabungan antara unsur profesionalisme yaitu ihsan, jihad, ilmu dan akhlak pokok (amanah dan ikhlas) untuk mendapatkan karya yang unggul[12], hal ini tersirat dalam firman Allah SWT pada QS.at-Taubah (9): 105, ayat ini menjelaskan, bahwa pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, dan akan diberitahukan serta diberi balasan atas amal dan perbuatan tersebut. Selain itu semua pekerjaan yang dilakukan dengan profesional atau itqan bagi setiap muslim sangat dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw dalam HR. Thabrani.[11]. Nilai-nilai khalifah dan nilai abd yang ada pada kepribadian dalam bekerja membentuk rajutan pada himmatul ‘amal. Nilai yang ada pada khalifah yaitu kreatif, produktif, inovatif dan konseptual. Sedangkan nilai yang ada pada abd adalah taat serta patuh pada syariah dan aturan pada masyarakat, karena itu etos dalam bekerja bukan semata-mata adalah bekerja tapi menjadi jihad fisabilillah. [13].
Karena itu himmatul ‘amal dalam Ekonomi Islam merupakan guideline tentang etos kerja, yang mensyaratkan bahwa kerja bukan saja semata-mata mencari rezeki tetapi lebih berdimensi transendental juga sebagai identitas kemanusiaannya. Jadi himmatul ‘amal dimaknai sebagai pandangan atau sikap manusia terhadap kerja yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini serta budaya dengan aturan tertentu. Karena itu dalam ekonomi Islam kegiatan muamalah yang dijalani adalah untuk mencapai maslahah yang merupakan substansi dari maqâsid al-syariah. Substansi ini merupakan prinsip kehidupan manusia terutama lima prinsip pokok dalam syariah atau hukum Islam, yaitu pemeliharaan agama (ad-dien), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl) dan harta benda atau al-maal, [14],[15],[16],[10],[17].
Memaknai hal diatas maka sudah seharusnyalah kita sebagai ummat Islam menunjukkan eksistensi kita dengan menjalankan
548 | New Normal, Kajian Multidisiplin
himmatul ‘amal di era new normal ini secara kaffah (total) atau secara menyeluruh, sesuai firman Allah dalam al-Quran ayat 208, yang “artinya masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syetan”. karena itu prinsip syariah di emban himmatul ‘amal khususnya substansi maqâsid al-syariah, yakni menjalankan ajaran agama (hifzuddien) dalam bekerja dengan penuh ketentraman dan ketenangan (hifzunnabal), agar ekonomi keluarga dapat terjaga.
Dilaksanakannya himmatul ‘amal secara kaffah akan dapat menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa (hifzun-nafs) baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, artinya istiqomah dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah sehingga dapat mengurangi angka kesakitan ataupun kematian. Pemeliharaan keselamatan jiwa dan menjamin kebebasan jiwa dalam Islam menjadi hal pertama terutama ketakutan terhadap kehidupan dan rezeki[16],[18]. dan jika dihadapkan dengan keadaan saat new normal, maka ini menjadi sangat prinsipil karena ekonomi Islam tidak hanya memaknai sisi ekonomi saja melainkan secara keseluruhan (kaffah) dan Islam mengajarkan untuk taqwa dan senantiasa beramal saleh, sebagaimana yang tersirat dalam QS. al-Hujarat (49):13.
Menegakkan nilai-nilai yang dapat menjamin untuk tetap mendapatkan pengetahuan berdasarkan ridho Allah SWT (hifz’aql) mengenai efek dan dampak dari kecerobohan yang dapat dilakukan selama adanya covid-19, membangun dan menjaga nilai-nilai yang dapat melindungi keluarga dan keturunannya (hifz-nasl) dari penyebaran wabah pandemi covid-19. Membangun nilai-nilai yang dapat menopang pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat dari akitivitas ekonomi yang saling menguntungkan (hifz-mall) dan yang diridhoi Allah. Membangun nilai-nilai yang santun dan bermoral dalam kebersamaan, saling tolong menolong dan bantu membantu baik individu maupun masyarakat saat ini dan masa mendatang.[19].
Menjalankan setiap kegiatan sesuai anjuran ekonomi Islam merupakan sarana atau jalan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, ini merupakan konsep falah yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan dan kekuatan serta harga diri.[20],[21]. Karena itu di dasari ayat dalam al-Qur’an maka nilai dan etika dalam himmatul ‘amal atau etos kerja Islam di maknai bahwa didalam bekerja setiap individu dihadapkan pada tiga tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap Allah SWT, tanggung jawab pada diri
New Normal, Kajian Multidisiplin | 549
sendiri dan tanggungjwab terhadap sesama atau orang lain.[16]. dengan penjabarannya berikut ini:
Tanggung jawab individu kepada Allah
Pemahaman pertama dari himmatul ‘amal mengenai tanggung jawab kepada Allah, adalah memaknai landasan bekerja karena iman, inilah yang medasari semua aktivitas kerja kita. Cerminan upaya yang dilakukan dengan mengingat Allah melalui shalat terlihat dari menghentikan kegiatan bekerja ditengah kesibukan, hal ini tergambar dalam firman Allah QS. ar-Rad:26, yang maknanya menunjukkan bahwa rezeki yang lapang bukan bukti kebahagiaan ataupun sebaliknya, tetapi kehidupan dunia hanya kesenangan yang sesaat.
Jika ini di maknai maka mengandung rahasia dan manfaat untuk ketenangan pikiran dan pengendalian diri yang bermanfaat sebagai proses relaksasi. Dan diharapkan istiqomah dilakukan agar bisa terjadi penjernihan pikiran, meningkatkan produktivitas dan optimalisasi hasil kerja, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. an-Nahl:97. Selain itu Allah juga akan melapangkan rezeki bagi ummatnya yang bersunguh-sungguh bekerja, sesuai makna yang tersirat dalam QS. al-Isra:30.
Karena itu di era new normal ini lebih meningkatkan makna petanggungjawaban kepada Allah atas setiap upaya yang dikerjakan dalam meraih rezeki, dan semoga motivasi kerja itu bisa timbul jika memaknai firman Allah dalam QS. al-Mulk:15. Bertanggung jawab pada Allah untuk bekerja mencari rezeki walaupun saat new normal, adalah bagian dari iman, sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah dalam QS. al-Mulk:15, untuk bergerak mencari rezeki ke penjuru bumi dan dianjurkan untuk memakan sebagian dari hasilnya, maksudnya dari sebagian hasil yang didapatkan itu adalah kita di anjurkan untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki untuk di sedekahkan, karena itu saat new normal ini sudah sepatutnya kita bersedekah, sebab pahala apapun yang dikerjakan akan dicatat dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) sebagaimana penjelasan dalam QS. Hud: 6, dan QS.al-Hajj: 35 yang menganjurkan untuk menafkahkan sebagian dari rezeki atau meng-infakkan sebagian rezeki yang di dapatkan atas karunia Allah SWT.
Pemahaman yang kedua penerapan himmatul ‘amal pada tanggung jawab individu kepada Allah, adalah selalu bersyukur, sebagai manusia kita senantiasa diperintahkan untuk mensyukuri semua rezeki yang diperoleh, karena rezeki itu tidak selamanya berwujud materi, bersyukur kepada Allah lahir dan bathin atas semua karunia yang telah diberikan,[22] dan ini diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah:172, ayat ini
550 | New Normal, Kajian Multidisiplin
bermakna pada kita umat Islam untuk memakan yang baik dari rezeki Allah dan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan.
Memperbanyak rasa syukur di era new normal ini adalah upaya sangat tepat, karena Islam juga mengajarkan kita sebagai manusia yang kaffah untuk selalu melihat ke bawah dengan memaknai nasib yang kurang baik agar jiwa menjadi tenang, karena rasa bersyukur akan mempengaruhi ketenangan jiwa dan meningkatkan rasa syukur akan menambah nikmat dalam hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ibrahim ayat 7 mengenai syukur yang akan menambah nikmat dan ingkar pada nikmat yang Allah berikan akan memberikan kepedihan. Selain itu, penambahan nikmat atas rasa syukur juga dijelaskan dalam QS. al-Kautsar:1. Adapun wujud dari rasa syukur adalah perintah untuk menunaikan shalat dan berkorban seperti yang dianjurkan dalam firman Allah QS. al-Kautsar: 2.
Tanggung jawab individu terhadap diri sendiri
Penerapan himmatul ‘amal pada tanggung jawab ini, yaitu memaknai bekerja sebagai kewajiban, bukan bekerja yang semata-mata bertujuan mendapatkan uang ataupun meminta-minta untuk mendapatkan uang, tetapi untuk membuktikan bahwa manusia adalah khalifah yang patuh dan tunduk mengikuti perintah Allah SWT, sebagaimana yang diriwatkan dalam HR.Muslim, yang artinya “seseorang yang keluar mencari kayu bakar (lalu hasilnya dijual) untuk bersedekah dan meghindari ketergantungan kepada manusia, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun ditolak”, dan hadits lain yang menyatakan bahwa “sesungguhnya tangan yang diatas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta).[11]. Jadi Islam mengajarkan untuk bekerja yang halal dan baik agar manusia dapat hidup secara sehat (thayyib dan halal). Selain itu, juga dianjurkan untuk menempuh jalan yang lurus (sirat al-Mustaqim) dan menjadi manusia yang bermanfaat serta ikhlas dalam beramal, ikhlas merupakan ciri orang yang berada pada jalan yang lurus sebagaimana yang di maknai dalam QS. al-Fatihah.
Hal yang tak kalah pentingnya di terapkan di era new normal ini adalah sikap sabar, terutama dalam menyikapi berbagai macam peristiwa maupun musibah, karena Allah akan memberi ujian ataupun cobaan pada hambanya untuk melihat tingkat kesabarannya, sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. al-Baqarah:155. Selain itu perintah bersabar atas apa yang menimpa kita juga di jelaskan dalam QS. al-Hajj: 35, QS. al-Ruum:37, QS. Lukman: 17 dan QS. al-Fajr:16, serta QS.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 551
al-Imran (3): 17, yang makna tafsirnya adalah perintah sabar dalam menghadapi cobaan yang menimpa dan rajin memanjatkan doa pada Allah di penghujung malam karena waktu tersebut doa mudah dikabulkan.
Karena itu manusia diminta bersabar dalam berbagai keadaan sesuai perintah dalam ayat tersebut. Dan jika manusia berdukacita dalam menghadapi kesusahan al-Qur’an juga telah memerintahkan untuk menunaikan shalat dan berdoa serta bersabar, yaitu pada QS. al-Baqarah: 45 dan 153. serta apabila ditimpa musibah hendaknya mengucapkan dan menghayati firman Allah dalam QS. al-Baqarah:156, artinya: “sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali”.
Islam mengajarkan untuk mengucapkan dan menghayati kalimat tersebut (istirja’) adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam berbagai situasi dan kondisi, terutama dalam masa pandemi ini untuk selalu bersikap:
1) sederhana, tidak boros dan tidak mubazir atau berlebih-lebihan. Hikmah pembelajaran dari adanya pandemik ini adalah pelajaran untuk disiplin mengatur pengeluaran di era new normal ini, untuk tidak memborong semua bahan pokok dan semua alat kebersihan karena mengikuti hawa nafsu belanja atau karena pemborosan (tabdzir). Padahal jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan adab untuk hidup tidak mubazir, sebagaimana yang diajarkan pada QS.al-Isra:26-27 bahwa orang-orang yang bersifat boros adalah saudara syaitan, serta tidak membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, seperti anjuran dalam QS. al-Furqan:67, juga penjelasan makna dari QS. al-Waqiah:41-45, yakni mengumpulkan barang-barang yang tidak di butuhkan dan prilaku hidup boros adalah bagian dari sifat orang kafir.
2) jujur dalam semua aspek kehidupan, di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa orang yang tidak jujur adalah orang yang menganiaya dan mendhalimi dirinya sendiri karena mengira menipu dirinya sendiri padahala Allah Maha mengetahui rahasia yang tersembunyi, hal ini di jelaskan dalam QS. al-Baqarah: 9. Dan jika dikaitkan era new normal ini, maka sangat di sayangkan jika masih ada oknum yang memberi keterangan palsu mengenai berita-berita yang sebenarnya terkait perkembangan pasien covid-19 yang meninggal ataupun sakit, juga termasuk permasalahan obat dan vaksin serta hal lain, karena Islam sangat menganjurkan untuk jujur dalam semua aspek kehidupan agar
552 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tidak terjadi penzaliman terhadap diri sendiri dan orang lain, sebagaimana makna dalam QS. Yunus:44.
3) berkeyakinan dan optimis. Jangan mudah terombang ambing ataupun ragu dan dipengaruhi, pendirian yang dimiliki haruslah dipegang teguh, sebagaimana yang di jelaskan dalam QS. al-Qalam:10, dan juga pada QS. al-Takaatsur (102):5 yang maknanya adalah memberikan tuntunan untuk bersifat optimis, memiliki tujuan dan memiliki informasi untuk orientasi masa depan. Selain itu juga al-Qur’an pada QS.al-Imran (3): 139, menjelaskan untuk tidak bersedih jika tertimpa musibah dan tetap harus optimis dengan ikhlas berpasrah pada Allah SWT, karena orang yang beriman adalah orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Selain itu Rasulullah juga bersabda dalam Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.,[11]. yang maknanya mengajarkan bahwa jika terkena suatu musibah atau kemalangan tidaklah mengatakan kata seandainya tapi berikhtiarlah bahwa itu adalah takdir dan kehendak Allah, sesuatu yang menjadi kehendak-Nya pasti akan terjadi. Karena itu sikap optimas haruslah dimiliki oleh setiap muslim, apalagi di era new normal ini sikap optimis dalam menghadapi wabah menjadi sesuatu yang mutlak karena Allah.
4) berupaya meningkatkan kualitas diri dan berilmu. Jika kita memiliki ilmu maka cenderung lebih bijaksana dalam menentukan sikap dan keputusan, karena orang yang berilmu akan menghasilkan tafakur yang berkualitas, sebagaimana firman Allah SWT pada QS. al-Muhjadilah: 11, yang maknanya bahwa orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah akan ditinggikan beberapa derajat, karena berilmu atau meningkatkan ilmu merupakan kapabilitas untuk melihat kemampuan seseorang. Jadi berilmu dan beriman maka akan menghasilkan kualitas kerja yang kaffah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini juga diisyaratkan Allah SWT dalam QS. al-Fatir: 28. Selain itu kualitas diri juga merupakan suatu kesungguhan yang artinya tidak menganggap remeh atau menyepelekan sesuatu, jadi adanya pandemic di era new normal ini tidak boleh dianggap remeh atau disepelekan, sebagaimana yg dimaknai dalam QS. an-Nur:15, artinya kita wajib bersungguh-sungguh menyikapi perilaku kita selama adanya wabah pandemic di era new normal ini, sebagaimana sikap bersungguh-sungguh yang dianjurkan dalam QS. al-Insyirah:7.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 553
5) bersifat waspada atau mawas diri. Sebagai seorang hamba yang beriman maka sudah seharusnya menanamkan sikap waspada atau sikap hati-hati atau mawas diri (hadzar) terhadap fitnah dan sejenisnya serta bencana, termasuk bencana dari adanya wabah covid-19 ini, sebagaimana pemaknaan dari QS. an-Nur (24): 63 yang mengingatkan untuk waspada terhadap cobaan ataupun fitnah, dan senantiasa mawas diri dalam berprilaku dan bertindak supaya terhindar dari segala macam azab atau hukuman dari Allah SWT. Karena itu di era new normal hendaklah menjalankan prilaku yang istiqomah atau konsisten mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan bersikap hati-hati agar dapat terhindar dari wabah covid-19.
6) bersih jasmani dan ruhani, kebersihan adalah milik orang sukses. Mengenai kebersihan, Islam sudah jauh lebih dulu mengajarkan dan Islam menempatkan manusia sebagai khalifah, karena itu dalam itu maqasid al-syari’ah disebutkan untuk menjaga jiwa (an-Nasf) dan menjaga akal (al-aql), serta menjaga keturunan (an-nasl), hal ini dimaksudkan adalah untuk menjaga kesehatan jiwa, menjaga kesehatan akal dan menjaga kesehatan keturunan, dan sudah termasuk di dalamnya menjaga kesehatan jasmani dan ruhani. Karena jika mengabaikan kebutuhan jasmani maka tentu saja kesehatan akan ikut terganggu, sebagaimana sabda Rasulullah dalam HR. Bukhari yang maknanya bahwa badan itu mempunyai hak atas dirinya.[23]
Kesehatan akan berjalan seiring dengan kebersihan atau dalam konsep Islam disebut dengan konsep taharah. Setiap muslim sangat dianjurkan untuk memperhatikan taharah (kebersihan), karena merupakan penentu dari kekhusukan shalatnya, sebagaimana sabda Rasulullah dalam HR. Muslim yang menyatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari Iman.[23]. Mungkin sangat arogan jika di analogikan bahwa jika tidak bersih maka tidak beriman, karena itu di era new normal ini tingkat kebersihan adalah suatu hal yang sangat urgent, sebagaimana anjuran dalam QS. al-Syams: 9-10 untuk membersihkan jiwa dan tidak berprilaku buruk dan tidak merugikan orang lain.
Secara kaffah kebersihan dalam Islam meliputi kebersihan harta dan jiwa, termasuk membersihkan perasaan, membersihkan kehidupan dan hubungan seks, membersihkan kehidupan masyarakat, serta menyucikan pandangan hidup dan amal perbuatan, inilah yang dinamakan tazkiyatun nafs. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa dalam
554 | New Normal, Kajian Multidisiplin
tazkiyah, harta dibersihkan melalui pengeluaran zakat, ataupun infaq serta sedekah[24],[25],[26],[23]. Dan penegasan infak termaknai dalam QS. al-Imran (3): 17, yakni orang-orang yang sabar dan taat kepada Allah akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Selain itu tazkiyah juga di gambarkan dalam firman Allah pada QS. an-Nisa (4):49 dan QS. As-Syams (91):9-10, yang maknanya bahwa Allah akan membersihkan hati siapa saja yang diinginkannya, dan menyebutkan bahwa orang yang mensucikan jiwanya adalah orang yang beruntung, dan akan rugi bagi yang mengotorinya.
Tanggung jawab individu terhadap sesama/ orang lain
Penerapan himmatul ‘amal yang pertama pada tanggung jawab ini terlihat pada fungsi sosialnya, yaitu wujud dari tidak kikirnya seseorang yang di manifestasikan berupa zakat dan infaq, hal ini telah di sabdakan oleh Nabi SAW dalam HR. Bukhari, yaitu: “Orang yang mengusahakan bantuan bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang yang sholat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tak pernah berbuka” (HR. Bukhari). Apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW dan yang di anjurkan dalam firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah:103, maka selayaknya di era new normal ini zakat, infak dan sadaqah lebih di intensifkan. Makna dari QS.at-Taubah: 103 dan QS. al-Imran (3): 17, yakni tentang zakat dan infak, mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki akan membersihkan dan mensucikan, serta kewajiban dalam mengeluarkan infak di jalan Allah.
Penerapan himmatul ‘amal yang kedua terlihat dari tanggung-jawab untuk mengucapkan dan berkata benar dan tidak mendustai kebenaran, ini digambarkan dalam QS. al-Lail (92):9. Juga memberi keterangan dengan adil dan benar jika bertindak sebagai saksi, ini digambarkan dalam QS. al-Ma’arij (70): 33, yang makna tafsirnya adalah jika melakukan suatu kesaksian maka jangan di pengaruhi oleh adanya unsur kekerabatan dan kedekatan ataupun karena sedang bermusuhan. Serta orang yang istiqomah dalam kesabaran dan taat dengan perkataan yang benar adalah orang-orang yang dikasihi Allah SWT, ini digambarkan dalam QS. al-Imran (3): 17. Atas dasar itu maka di era new normal ini penerapan tentang berkata benar dan tidak mendustai kebenaran terutama berbohong atau tidak menutup-nutupi adanya penularan covid-19 di suatu kluster atau di suatu keluarga adalah suatu keharusan, karena akibatnya akan fatal.
Adapun penerapan himmatul ‘amal ketiga pada tanggung jawab sesama atau pada orang lain, yaitu tidak bersifat hasad, tidak bakhil,
New Normal, Kajian Multidisiplin | 555
amanah, adil dan pemaaf, serta jika melakukan transaksi harus ada syarat, akad dan saling rida, dan menghindari beberapa larangan dalam transaksi, hal ini sangat jelas diisyaratkan dalam firman Allah pada QS. an-Nisa (4):29, yang dimaknai bahwa orang yang beriman tidak akan saling memakan harta sesama di jalan yang batil namun akan berniaga dengan cara suka sama suka. Dan mengenai sifat bakhil atau sifat kikir di gambarkan dalam QS. al-Isra:100, bahwa sifat bakhil akan timbul disaat memiliki harta yang cukup dan keimanan akan di uji, apabila mampu mengeluarkan sebahagian harta yang dimilikinya untuk berbagi dengan sesama, maka akan terhindar dari kecintaannya pada dunia (wahn).
Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai hak dan kewajiban untuk bersosialisasi dan bermasyarakat ataupun bermuamalah karena itu tanggung jawab amanah dan adil merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan terutama pada lingkup organisasi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. an-Nisa:58, yang maknanya adalah Allah SWT memberi penegasan dan pengajaran bahwa amanah harus disampaikan kepada yang wajib menerimanya, dan apabila menetapkan hukum maka lakukan dengan adil, dan Allah Maha melihat atas apa yang dikerjakan.
Sebagai manusia yang hidup bersosial dan berorganisasi baik di tempat kerja atau dimanapun tentu pernah di hadapkan pada suatu rasa bersalah ataupun khilaf, ataupun orang lain pernah berbuat salah pada dirinya, maka dalam hal ini Islam telah memberikan ajaran dan tuntunan mengenai pemberian maaf dan menjadi pemaaf serta tidak menjadi pendendam, sebagaimana yang diajarkan pada QS. Fussilat:34-35. Selain itu juga di gambarkan dalam QS. al-Imran:134, yang mengajarkan bahwa orang yang bertaqwa, yaitu orang mampu menahan amarahnya dan tidak membalas pada orang yang telah menzaliminya dan mampu memafkannya, maka Allah menjanjikan ampunan dan surga baginya. Karena itu di era new normal ini meningkatkan rasa memafkan sangat wajib dijalankan terutama di dalam keluarga dan organisasi, karena di masa ini ada saja masalah yang dapat memicu konflik perselisihan keluarga seperti kekerasan psikologis, stress karena berkurangnya penghasilan ekonomi, ini terlihat dari tingginya tingkat perceraian antar suami dan istri di masa pandemic ini yang ditunjukkan dengan angka 1.012 pada bulan Juni pengajuan gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung.[27].
Penutup
Di era normal ini sangat penting untuk memotivasi masyarakat agar kembali ke fitrah sebagai muslim yang kaffah (menyeluruh)
556 | New Normal, Kajian Multidisiplin
sebagaimana yang di perintahkan Allah SWT. Karena itu implikasinya adalah menerapkan himmatul ‘amal dalam kesehariannya dengan memberi pemahaman bahwa Islam mendorong ummatnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam bekerja baik itu tanggungjawab kepada Allah, tanggung jawab kepada diri sendiri ataupun tanggung jawab kepada sesama. Karena itu dalam menjalankan aktivitas sosialnya bermasyara-kat ataupun bekerja dalam kehidupan sehari-hari agar selalu istiqomah atau konsisten mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
Sebagai langkah utama adalah melaksanakan himmatul ‘amal secara kaffah dan istiqomah dengan meyakinkan diri, bahwa bekerja dan menjalankan ajaran agama (hifzuddien) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam bekerja akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dengan demikian ekonomi keluarga dapat dijaga. Kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai yang dapat memelihara keselamatan dan kesehatan jiwa (hifzun-nafs) baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat, sehingga di era new normal ini dapat saling membantu dan melindungi dari ketakutan hidup dan ketakutan rezeki. Ketiga, menegakkan nilai-nilai untuk menjamin dalam mendapatkan pengetahuan (hifz’aql) yang di ridhoi Allah SWT agar manfaat dan berkah dalam bekerja. Keempat, menjaga nila-nilai yang dapat melindungi dan menjaga kesehatan keluarga dan keuturunan (hifz-nasl) dari penyebaran wabah Covid-19. Kelima, membangun nilai-nilai yang dapat menopang pengembangan ekonomi keluarga atau masyarakat (hifz-mall) dengan hasil kerja yang saling menguntungkan dan saling ridho. Jadi semua aktivitas kerja ataupun berkegiatan yang dilakukan selama pandemi maupun setelah pandemi haruslah merupakan sarana untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl: 97.
Rujukan
[1] A. Pragholapati, “New Normal ‘Indonesia’ After Covid-19 Pandemic,” 2020.
[2] R. C. Chen, T. T. Tan, and L. P. Chan, “Adapting to a new normal? 5 key operational principles for a radiology service facing the COVID-19 pandemic,” Eur. Radiol., p. 1, 2020.
[3] J. Timotijevic, “Society’s ‘New Normal’? The Role of Discourse in Surveillance and Silencing of Dissent During and Post Covid-19,”
New Normal, Kajian Multidisiplin | 557
2020. [4] Q. Syihabuddin, “Prinsip New Normal Dijelaskan Rasulullah 14
Abad Silam,” www.republika.co.id, 2020. [5] V. Kasiano, “Peringatan Dini New Normal di Indonesia Bisa
Prematur,” 2020. [6] G. Lawton, “The new normal,” New Sci., vol. 241, no. 3213, pp. 34–
37, 2019. [7] A. Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19,” ’ADALAH, vol. 4, no.
1, 2020. [8] F. Fanani, “Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di
Indonesia,” www. merdeka.com, 2020. [9] T. Tasmara, Membudayakan etos kerja Islami. Gema Insani, 2002. [10] B. M. Ramadhan and M. N. H. Ryandono, “Etos kerja Islami pada
kinerja bisnis pedagang muslim pasar besar kota Madiun,” J. Ekon. syariah Teor. dan Terap., vol. 2, no. 4, 2015.
[11] I. Harahap, Hadis-hadis ekonomi. Prenada Media, 2017. [12] S. Hendrawan, Spiritual Management. PT Mizan Publika, 2009. [13] A. A. Janan, “Etos Kerja Islami.” Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2004. [14] Y. Al-Qaradawi, “Dirasah fi Fiqh Maqasid Shari’ah,” Kaherah Dar
al-Shuruq, 2006. [15] Al-Syatibi, Al-Muawafaqat di Usul Al-Syari’ah Jus 1. Kairo: Dar al-
Taufiqiyyah, 2003. [16] S. S. bin N. al-U. Quthb, Sayyid, Abdullah Azzam, Al-Mustaqbal
Lihadza Ad-Din Al-Islam wa Mustaqbal Al-Basyariyyah Ala Inna Nasharralah Qarib, Terj. Abu Nadidah Humaero dan Abu Ja’far Al-Indunisy. Solo: Media Islamika, 2009.
[17] M. Rusfi, “Mqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi,” Asas, vol. 10, no. 02, pp. 23–45, 2019.
[18] H. Aravik, “Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb,” Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah, vol. 3, no. 2, pp. 31–43, 2018.
[19] N. Hidayanti, “Front Pages Inderaja Vol. 14 No. 2 Desember 2017,” J. Penginderaan Jauh dan Pengolah. Data Citra Digit., vol. 14, no. 2, 2017.
[20] M. U. Chapra, The future of economics: An Islamic perspective, vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
[21] K. Irwan, “Apa Arti Falah Dalam Ekonomi Islam,” www. republika.co.id, 2017.
[22] M. Q. Shihab, “Tafsir al-misbah,” Jakarta lentera hati, vol. 2, 2002.
558 | New Normal, Kajian Multidisiplin
[23] M. Fitriah, “KAJIAN AL-QURAN DAN HADITS TENTANG
KESEHATAN JASMANI DAN RUHANI,” TAJDID J. Ilmu Ushuluddin, vol. 15, no. 1, pp. 105–126, 2016.
[24] A. A. Karzan and E. Threeska, Tazkiyatun nafs: gelombang energi penyucian jiwa menurut al-Qur’an dan as-Sunnah di atas Manhaj Salafus Shaalih. Akbar Eka Sarana, 2010.
[25] A. Farid, Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa dalam Islam. Penerbit: Umul Qura, 2018.
[26] M. Syamsuddin, “TAZKIYATUN NAFS DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN,” www.tunailmu. blogspot.com, 2016. .
[27] F. C. Kurniawan, “Penyebab Angka Perceraian Meningkat Selama Pandemi Covid-19,” www.merdeka.com, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 559
Bab 35
Lonjakan Gugatan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Apakah Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Utamanya? Mochamad Ridwan40
Pengantar
Bermula dari informasi Kepala BKKBN provinsi Jawa Barat di media televisi RCTI tanggal 1 September 2020 bahwa selama pandemi Covid-19 telah terjadi lonjakan secara tajam gugatan perceraian istriterhadap suami di kawasan provinsi Jawa Barat sebesar 20%. Munculnya fenomena mengejutkan ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan seperti, mengapa gejala yang anomalistik ini bisa terjadi? faktor apa yang dapat memicunya? atau apakah faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya?. Fenomena seperti ini, dalam pandangan sederhana (common sense) agak bertentangan dengan kondisi yang normal. Seharusnya wabah/pandemi Covid-19 ini menjadikan perilaku masyarakat lebih konservatif (bersikap lebih hati-hati) atau meredam segala perilaku yang kontroversial atau kontradiktif seperti perilaku sosial berupa gugatan perceraian seperti yang terungkap dalam berita media televisi RCTI tersebut [5].
Secara common sense, fenomena sosial perceraian pada umumnya dipicu atau dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga, misalnya karena dampak rasionalisasi tenaga kerja dari pekerjaannya (terjadinya pengangguran). Fenomena sosial seperti ini terjadi sebagai akibat dari semakin lesunya kondisi perekonomian atau turunnya kinerja ekonomi secara signifikan (sebagai contoh sebagai dampak pandemi Covid-19). Seirama dengan fenomena terjadinya lonjakan angka gugatan perceraian seperti kasus yang terjadi di Jawa Barat ini, salahsatu penyebabnya bisa dipicu atau dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam bentuk ketidakterpenuhan kebutuhan nafkah istri yang seharusnya diberikan oleh suami. Faktor-faktor lain (selain faktor ekonomi) juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu (faktor penyebab) terjadinya lonjakan perceraian ini. Jika jawabannya adalah faktor ekonomi yang menjadi pemicunya, maka yang perlu diidentifikasi adalah bentuk faktor ekonomi yang bagaimana, dari kluster (kelompok) sosial ekonomi yang mana yang
40 Dr. Mochamad Ridwan, Dosen Universitas Bengkulu
560 | New Normal, Kajian Multidisiplin
terbanyak mengajukan perceraian, dan masih banyak pertanyaan lain yang dapat muncul di sini [5], [9].
Pandemi covid-19 merupakan fenomana social berupa penyebaran wabah yang awalnya berasal dari negeri China dan masu ke Indonesiasekita enam bulan yang lalu. Hingga kini hampir seluruh negara di dunia telah perpapar virus tersebut. Kendati jumlah orang yang terpapar cukup besar, namun Alhamdulillah jumlah yang dinyatakan sembuh (dinyatakan negative juga cukup besar. Proses upaya untuk menganggulangi senantiasa terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan semakin berunculan vaksin anti corona-19 telah dirilis, bahkan banyak yang klaim ditemukana obat corona, begitu juga berbagai metode preventif untuk menghindari menyebarnya wabah ini semakin meluas, metode “herd immune” telah disosialisasikan ke masyarakat terutama pada era “new normal” ini [8].
Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja dan lapangan usaha secara kasat mata sangat bisa dirasakan. Turunnya produktivitas kerja akibat diberlakukannya sistem kerja WFH (Work from Home) dan mandegnya sebagian besar dunia usaha cukup bisa dirasakan khususnya di Indonesia. Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap melonjaknya angka pengangguran terbuka (open unemployment) akibat adanya rasionalisasi dari pekerjaannya atau berhentu melakukan dunia wirausaha karena permintaan barang atau jasa yang menurun secara signifikan. Turunnya kinerja ekonomi yang cukup signifikan telah berdampak menurunnya tingkat pengupahan dan pendapatan dari para tenaga kerja di dunia pekerjaan swasta. Tentu hal ini bisa berdampak terhadap turunnya kemampuan para kepala rumah tangga yang sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga dalam mencukupi kebutuhan keluarganya [6]-[7], [10].
Dalam kasus melonjaknya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 di Jawa Barat sekitar 20% tersebut, sebuah kajian atau review penting untuk dilakukan guna mengungkap secara mendalam terjadinya fenomena ini. Sehingga pada gilirannya diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang bermanfaat dan berguna bagi masukan dan balikan dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang harus ditetapkan di masa mendatang (di masa normal baru) pasca pandemi Covid-19. Melalui kajian atau review dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan akan dapat mempertajam cara berfikir lebih kritis dan lebih bijak dalam menyongsong kehidupan di era “new normal” yang lebih bermakna dan bermanfaat [5].
New Normal, Kajian Multidisiplin | 561
Pembahasan
Fenomena Perceraian sebagai Fenomena Sosial Berbingkai Fenomena Ekonomi Empiris
Dalam diskursus ilmu ekonomi baik secara makro maupun mikro, permasalahan sosial seringkali dikaitkan dengan permasalahan ekonomi, artinya fenomena atau faktor sosial lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi ketimbang oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu tidak salah jika ada pernyataan yang muncul bahwa permasalahan sosial yang terjadi, penyeba utamanya atau penyebab awalnya (causa prima) adalah faktor ekonomi. Kajian makroekonomi cenderung menitikberatkan pada pemikiran secara agregatif, sedangkan kajian mikroekonomi lebih menitikberatkan pada analisis pasar (analisis permintaan dan penawaran pasar). Secara kontekstual, fenomena perceraian yang terjadi cenderung disebabkan oleh faktor makroekonomi, yang dapat dianalisis melalui mekanisme kekuatan-kekuatan yang terjadi pada sisi permintaan dan penawaran secara agregat (Aggregate Demand dan Aggregate Supply) [1], [7], [9].
Secara kontekstual, mekanisme terjadinya kasus gugatan perceraian berawal dari kebutuhan keluarga dalam bentuk materi yang belum tercukupi. Dalam konsep permintaan agregat (aggregate demand/AD), kondisi ketidak ketercukupan materi ini dicerminkan melalui penurunan pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga (C). Dengan asusmsi ceteris paribus, maka berdasarkan persamaan permintaan agregat (aggregate demand/AD) yakni Y = C+I+G+(X-M), maka dampak berikutnya yang terjadi adalah terjadinya penurunan pendapatan (Y) akibat dari semakin kecilnya efek pengganda (multiplier effect) faktor konsumsi rumah tangga. Penurunan pendapatan ini diawali dengan terjadinya pergeseran kurva permintaan agregat (shifting of aggregate demand curve) ke arah kiri bawah [1], [9].
Dilihat dari konsep ekonomi ketenagakerjaan, fenomena tersebut mengindikasikan terjadinya pengangguran siklikal atau pengangguran yang disebabkan karena adanya imbas dari naik turunnya siklus ekonomi (terjadi karena ada penyempitan permintaan akan tenaga kerja). Peningkatan pengangguran ini mengindikasikan adanya konsekuensi semakin menurunnya kemampuan penerima pendapatan (diproksikan oleh suami sebagai kepala keluarga) dalam mencukupi kebutuhan keluarga (termasuk di dalamnya nafkah lahir/keuangan untuk istri). Ketidakkecukupan nafkah lahir untuk istri ini acapkali menyulut
562 | New Normal, Kajian Multidisiplin
rangsangan terjadinya tuntutan perceraian dari istri kepada suami. Keterkaitan yang penting di sini adalah ditunjukkannya peran penting dari pengelolaan pendapatan keluarga yang efektif, sehingga tidak berpeluang memunculkan sikap-sikap yang anomalistik-seperti muncul-nya keinginan melakukan gugatan peerceraian. Kata efektif di sini dapat dimaknai sebagai pengelolaan pendapatan keluarga yang sesuai dengan koridor untuk pencapaian tujuan dan harapan keluarga [8].
Analisis Kritis Permasalahan Gugatan Perceraian dengan Motif Ekonomi
Pengaruh kebutuhan istri akan materi terhadap kecenderungan melakukan gugatan perceraian seperti dijelaskan sebelumnya, melalui pendekatan mikroekonomi dapat dijelaskan dengan menganalisis hubungan interaktif antara dua barang yang harus dipilih dalam kurva indiferen (indifference curve), di mana tingkat kepauasan tertentu dapat diraih oleh seseorang ketika dia harus memilih antara dua barang yang akan dibelinya agar memperoleh kepuasan maksimum dengan kendala anggaran yang dimiliki [1], [9].
Ibarat pendapatan suami untuk istri dan keluarga adalah sebuah anggaran dengan sejumlah tertentu, maka mau tidak mau untuk mendapatkan kepauasn maksimum maka sang istri harus mampu memanfaatkan konsumsinya pada dua pilihan kelompok pengeluaran konsumsi untuk keluarganya sedemikian rupa. Secara skematis mekanisme pembelanjaan anggran keluarga (rumah tangga) dalam bingkai modifikasi pendekatan mikroekonomi (indifference curve approach) dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1: Kepuasan/Kebahagian Maksimum dari Pasangan
5 10 15 20
25 335 40
0 5 10 15 20 25 30 3 40 Jumlah Kebutuhan Keluarga I
Jum
lah
Ke
bu
tuh
an
Ke
luar
ga II
a
b c
d e f
Anggaran (Nafkah)
New Normal, Kajian Multidisiplin | 563
Gambar 1 memperjelas bagaimana kasus gugatan perceraian yang muncul dikarenakan nafkah untuk kebutuhan keluarga (istri) dirasakan (dianggap) belum cukup, sehingga dianggap belum mampu memberikan kepuasan/kebahagiaan yang diinginkan keluarga (istri). Dalam bahasan mikroekonomi (analisis kurva indiferen), Gambar 1 merupakan kurava modifikatif dari keseimbangan antara kurva indiferen (digambarkan oleh alternatif pilihan keseimbangan/kepuasan/kebahagian yang diperoleh keluarga dengan melakukan pilihan anggaran/nafkah terhadap dua pilihan kebutuhan keluarga). Kepuasan/kebahagiaan maksimum yang diperoleh keluarga/istri berada pada titik b, di mana kebahagian diperoleh dengan cukup mengkonsumsi (membelanjakan) anggarannya pada kebutuhan I sebanyak 10 unit dan kebutuhan II sebanyak unit 15,5 unit. Dalam konteks keseimbangan kurva indiferen, keinginan melakukan gugatan perceraian diilustrasikan mereka yang tidak berada pada titik keseimbangan (titik singgung antara kurva indiferen dengan garis anggaran (nafkah untuk keluarga/istri). Bisa jadi garis anggaran (nafkah lahir/materi) berada di bawah kurva indiferen atau bisa jadi berada di atas kurva indiferen, di mana di kedua posisi ini istri cenderung melakukan gugatan perceraian terhadap suaminya [1], [9].
Penutup
Menelusuri kasus lonjakan gugatan perceraian selama masa pandemi Covid-19, nampak bahwa kecenderungan secara ekonomi dapat dijelaskan/dianalisis dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan dengan pendekatan makroekonomi, sedangkan pendekatan kedua dilakukan dengan pendekatan mikroekonomi. Melalui pende-katan makroekonomi, lonjakan gugatan perceraian disebabkan oleh faktor terjadinya rasionalisasi tenaga kerja (terjadinya pengangguran siklikal atau konjungtural), di mana semakin mengecilnya faktor konsumsi rumahtangga berdampak terhadap bergesernya kurva permin-taan agregat ke kiri bawah sehingga membuka pintu pengangguran yang semakin melebar, yang berakibat munculnya gugatan perceraian istri kepada suami. Pendekatan kedua dilakukan melalui pendekatan mikroekonomi yaitu pendekatan kurva indiferen, di mana anggaran (nafkah materi/lahir) tidak mampu bersinggungan dengan kurva indifferen (indifference curve) atau tidak terjadi kepuasan/kebahagiaan yang maksimum. Sehingga menyebabkan istri berkecenderungan melakukan gugatan perceraian kepada suami. Oleh karena itu saran solusi kritis yang dapat diberikan adalah mengarahkan kepada pasangan suami istri agar senantiasa kembali ke perspektif bahwa kebutuhan suami
564 | New Normal, Kajian Multidisiplin
istri dan keluarga/rumah tangga yang esensial adalah kebutuhan kebahagiaan, keharmonisan, kebutuhan cinta kasih, dan kebuhtuhan ketenangan (tersurat dan tersirat dalam Q.S. Ar-Ruum: 21) [4].
Rujukan
[1] Akhmad. “Ekonomi Mikro-Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha”, Penerbit Andi Offset (ISBN:978-979-29-2353-7), (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2014.
[2] CNNIndonesia.”194109-positif-138575-sembuh”,https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200906122739-20-543303/ 6 September 2020.
[3] Hanoatubun, Silpa. “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”, Journal of Education, Psychology and Counseling (EduPsyCouns Journal), Volume 2, Nomor 1 (2020), ISSN Online : 2716-4446, Halaman: 146-153, 2020.
[4] Hatta, Ahmad. “Tafsir Qur’an Perkata”, Penerbit Maghfirah Pustaka (ISBN:978-979-1026-80-2), Jakarta, 2009.
[5] Kusmana. “Kepala BKKBN Jawa Barat dalam RCTI-News Siang: Kasus Perceraian Di Tengah Pandemi Covid-19”, Jakarta, 1 September 2020.
[6] Mas’udi, Wawan dan Winanti, Poppy S. “Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal”, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2020.
[7] Modjo, Mohamad Ikhsan. “Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi”, The Indonesian Journal of Development Planning”, Volume IV, No. 2, Halaman:103-116, Juni 2020.
[8] Muhyiddin. “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, The Indonesian Journal of Development Planning”, Volume IV, No. 2, Halaman: 240-252, Juni 2020.
[9] Priyono dan Ismail, Zainuddin. “Teori Ekonomi”, Zifatama Publishing (Anggota IKAPI No.149/JTI/2014, Surabaya, 2016.
[10] Soetjipto, HM. Noer. “Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19”, Penerbit K-Media (Anggota IKAPI No. 106/DIY/2018), Yoyakarta, 2020.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 565
Biodata Penulis
ABD. MUHITH, Lahir di Bondowoso tepatnya 16 Oktober 1972, Muhith, sapaan akrabnya, memulai karir dari seorang penjaga MIN dekat rumah masa kecilnya. Ia adalah seseorang dengan dedikasi yang tinggi dalam menekuni bidang yang ia sukai yakni menjadi seorang akademisi. Sejak pindah ke IAIN Jember (2016) beliau berkomitmen untuk selalu me-ningkatkan tingkat produktivitas diri. Baginya, usia tak membatasi raganya untuk terus berkarya. Terbukti hingga kini sudah lebih dari 40 karya tulis baik buku, jurnal, maupun bunga rampai yang telah ia ciptakan. Tak pelak, ia juga telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi.
ABUSTAN Lahir di Bone, 27 Mei 1962, Pekerjaan yang pernah ditekuni adalah menjadi Advokat Praktek selama sekitar 20 tahun, menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (1999-2004), tenaga ahli pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2010-2012), Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional 2013-2016, Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPD-RI (2017-2019), Kini Dosen tetap Fakultas Hukum dan Pasca Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta. Dengan sertifikat pendidik Nomor Registrasi 19103100300475, juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, Pendampingan (Legal Opinion), mengikuti pelatihan dan seminar nasional/internasional.
ADISSYA MEGA CHRISTIA, lebih akrab disapa Adissya, lahir di Jember, 25 Februari 1997. Pada tahun 2014 pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bagian Hukum Kenegaraan lulus pada tahun 2019 sebagai lulusan terbaik. Minatnya pada hukum kenegaraan didasarkan pada keyakinan bahwa Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang menjamin kesempatan yang sama serta hak dan kewajiban yang seimbang bagi seluruh rakyat tanpa boleh ada diskriminasi dan intoleransi dengan Pancasila sebagai ideologi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti meliputi Bendahara I Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan Bendahara I Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Buku yang telah diterbitkan berjudul Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan
566 | New Normal, Kajian Multidisiplin
AGUS YUWONO dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Lahir di Ngawi, 15 Desember 1968. Jabatan Lektor kepala. Kepakaran penulis di bidang: Telaah Kurikulum, Penulisan Buku Teks, dan Micro Teaching. Banyak melakukan penelitian dan pengabdian, baik yang didanai oleh lembaga UNNES maupun bersumber dari DIKTI. Penelitian dan pengabdian penulis terkait dengan pembelajaran seperti pengembangan kompetensi guru, pengelolaan kelas, pengembangan media pembelajaran, dan lainnya, email: [email protected]
A. IFAYANI HAANURAT lahir di Ujung Pandang 3 Agustus 1966. Memutuskan untuk menggeluti dunia akademik adalah saran dari ibunda tercinta yang juga pengurus Aisyiah di masanya, Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 1990, menjadi praktisi kurang lebih dua tahun di perusahaan swasta di Jakarta sambil studi S2 tahun 1997 pada Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia Y.A.I., dan menyelesaikan studi S3 program Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga tahun 2013. Akhir tahun 1997 bergabung menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muham-madiyah Makassar. Tahun 2006 menerima penghargaan sebagai Dosen Berprestasi tingkat Unismuh dan tahun 2007 sebagai Dosen Berprestasi III Tingkat Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Diamanahi menjadi Ketua Tim Pendiri Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh tahun 2007, dan tahun 2008 menjadi wakil dekan bidang keuangan dan administrasi, tahun 2010 menjadi Direktur Eksekutif project hibah FK, program HPEQ PHK-PKPD. Tahun 2017melalui project kerjasama Unismuh dengan Humber College Canada: Sulawesi Economic Development Strategy Project mengikuti workshop Entrepreneur kurang lebih empat tahun dan lolos sampai tahap akhir serta mendapat penghargaan profesi sebagai Certified Business Coach, kemudian menjadi KPS MM program S2, akhir tahun 2018 menjadi Wakil Direktur bidang kerjasama Pascasarjana. Tahun 2019 mendapat sertifikat keahlian kecakapan profesi Pasar Modal dari The Indonesia Capital Market Institute sebagai WPPE. Atas pengalaman dan jalinan kerjasama bisa mendirikan dan membina Galeri Investasi tahun 2016 bersama Bursa Efek Indonesia dan PT. Phintraco Sekuritas, dan menghantarkan sebagai Terbaik dan Terinovasi tingkat Nasional. Tahun 2019 memberikan edukasi pelatihan pengelolaan startup bisnis program BUMDES se-Kabupaten Banggai Saat ini aktif menulis dan membantu startup bisnis mahasiswa dan anggota Asosiasi profesi FDK, FMI MASEI, IAEI, AMCA.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 567
AKHSANUL IN’AM, lahir di Kediri 10 Agustus 1964, keseharian menggeluti peningkatan profesionalisme guru sebagai aktivitas untuk berbagi mengembangkan dan meningkatkan kualitas insan. Jabatan yang diraih sebagai dosen adalah Guru Besar Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, dan sekarang menjadi Direktur Program Pascasarjana Uni-versitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga sebagai Ketua Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang juga sebagai Pengurus Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Email: [email protected]
AKRIM, lahir di Muara Mais Sumatera Barat 22 Desember 1979, menjadi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2004, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Menempuh pendidikan S1 di UMSU Program Studi Pendidikan Agama Islam lulus tahun 2003, S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan lulus tahun 2008, S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2020. Memiliki Publikasi pada Jurnal Internasional Terindkes Scopus Q2 (Penulis Pertama); Utopia Y Praxis Latinoamericana, Revista International, De Filosofia Y Teoria Social. p-ISSN: 1315-5216. e-ISSN: 2477-9555. pp. 132-141. Berjudul: Daily Learning Flow of Inclusive Education for Early Childhood. Memiliki buku dengan judul Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam yang diterbitkan pada tahun 2020. Saat ini menjadi chief editor Internasional Journal Education and Mathematic Sciences.
AMIRUL WAHID RWZ, Didikan keras dari orang tua tak membuat Wahid patah arang untuk menggapai cita-cita. Dari seorang remaja ingusan yang tidak mengerti dunia tulis menulis, ia telah bermetamor-fosa menjadi seorang penulis partikelir. Motto hidupnya adalah “Everyone is teacher, everywhere is learning”. Tulisanya dapat dinikmati di berbagai media digital dan cetak tingkat nasional.
ARWIN JULI RAKHMADI BUTAR-BUTAR, Lahir 20 Juli 1980 di Buntu Pane, Asahan Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 jurusan Syariah di Universitas Islam Sumatera Utara, S2 & S3 jurusan Filologi Astronomi di Institute of Arab Research and Studies Cairo, Mesir. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan diamanahi sebagai Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara spesialis keilmuan-nya ilmu falak, naskah manuskrip dan filologi astronomi.
568 | New Normal, Kajian Multidisiplin
ASNGADI, dosen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pendidikan Sarjana, ditamatkan di Univer-sitas Tadulako, 2007; Magister ilmu Manajemen, Universitas Airlangga tahun 2003; Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Brawijaya tahun 2017. Bidang ilmu yang menjadi peminatan adalah Manajemen Operasi dan Manajemen strategik. Beberapa organisasi afilisai yang diikuti adalah ISEI; Forum Manajemen Indonesia; AMCA (Association of Moslem Community in ASEAN). Selain aktif di beberapa asosiasi, juga menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional terindeks sinta yakni Journal akuntansi bisnis dan manajemen, STIE Malangkucecwara, Malang; Jurnal CRMJ Universitas Hazairin, Bengkulu; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas ekonomi universitas Syahkuala; dan internasional: Asian Journal of Advances in Research, MB International Media and Publishing House, India. Beberapa penelitiannya terbit di beberapa jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindes DOAJ/ Copernicus /crossreff; jurnal nasional terindeks sinta. Selain termuat di bebeapa jurnal nasional dan internasional, beberapa tulisan juga terbit di prosiding internasional terindek thomson reuter dan scopus.
A SUHARDI, lahir di Bone tanggal 15 September 1973, merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan H. Andi Maming dan Hj Andi Puttiri, semasa pendidikan menamatkan pendidikan dasar di SD Inpres Bulurokeng Makassar tahun 1986, menamatkan pendidikan menengah di SMPN 9 Makassar tahun 1989, dan menamatkan pendi-dikan atas di SMAN 6 Makassar 1992. Pendidikan sarjana di selesaikan di jurusan Teknik Kimia fakultas Teknologi Industri tahun 1999, menyelesaikan program magister pada Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Malang tahun 2005, dan menyelesaikan program doktor di program studi Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang tahun 2015. Saat ini aktif sebagai dosen program studi Tadris IPA FTIK IAIN Jember dan diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Karya-karya di bidang ilmiah aktif menulis jurnal sinta dan sekaligus sebagai reviewer di jurnal INSECTA IAIN Ponorogo
BULKANI lahir di Buntok, tanggal 14 September 1969. Menamatkan pendidikan MIN hingga SMA di Buntok, dan melanjutkan pendidikan S1 ke Universitas Palangka Raya pada program studi Pendidikan Matematika sebagai mahasiswa penerima Tunjangan Ikatan Dinas. Melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan program S3 di Universitas Negeri Jakarta pada program studi Penelitian
New Normal, Kajian Multidisiplin | 569
dan Evaluasi Pendidikan. Selain berkarir sebagai dosen dpk di UM Palangkaraya, juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di Kalteng, antara lain sekretaris PW Muhammadiyah, sekretaris umum MUI, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit se-Propinsi Kalteng, Ketua Harian DMI, dan wakil ketua Dewan Adat Dayak Kalteng. Selain aktif menulis tulisan pendek dan opini di harian Kalteng Pos. juga menulis beberapa buku, antara lain Untung Masih Ada Lupa, Program Green Islamic Campus Menjawab Isu Lingkungan dan Radikalisme, Statistika Parametrik, dan Pukung Pahewan Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia.
DAROE ISWATININGSIH, lahir di Surabaya, 25 Agustus 1965. Memula karir di UMM pada 1990 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, sebagai dosen LLDIKTI yang diperbantukan. Saat ini jabatan fungsionalnya Lektor Kepala Pembina Utama Muda pada Gol. IVc. Keaktifan dalam organisasi profesi sebagai sekretaris HISKI Komisariat Malang (2016-sekarang), anggota HPBI, Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan APPBIPA Jawa Timur, serta Pemimpin Redaksi Jurnal Satwika, Lembaga Kebudayaan UMM. Mata kuliah yang pernah diampu di S1, Belajar dan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, strategi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, dan Analisis Wacana. Adapun di S2, Kajian Makro Linguistik dan Menulis Ilmiah. Melakukan kegiatan Tri Darma perguruan tinggi secara aktif. Saat ini jabatan fungsional Lektor Kepala Pembina Utama Muda pada Gol. IVc. Bidang penelitian, khususnya menulis artikel ilmiah menjadi perhatian utama agar dapat lolos pada jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Telah melakukan kunjungan ke sembilan negara untuk kegiatan akademik, tiga di antaranya mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan oleh AMCA (Association Moslem Community in Asean) (2017-2019)
DIAN EKA CHANDRA WARDHANA, Memiliki ID Scopus dengan No 57211549856, ID ORCHID 0000-0002-8424-0153, ID Google Scolar LskMdgAAAAJ, ID Shinta 5985344. Lahir di kota Malang 4 November, dan dikaruniai putra-putri 3 orang, dan 3 cucu. Menjadi Dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Bengkulu sejak tahun 1984, meraih gelar Doktor tahun 2006. Artikel-artikel yang sudah dipublikasikan sekitar 115 artikel (Google Scoler) dan H-index 2 (6 artikel di jurnal internasional serta jurnal internasional bereputasi). Kegiatan pengampuan pembelajaran di matakuliah Bahasa Indonesia (MKU), Psikolinguistik, Wacana, dan Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia,
570 | New Normal, Kajian Multidisiplin
dan kegiatan penelitian di bidang Wacana Bahasa dan Sastra Indonesia serta pengajarannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang wacana dan pendidikan serta pengajaran Bahasa IndonesiaAwal PNS di PTN (1984-1986), mengampu matakuliah Bahasa Indonesia sebagai matakuliah Kepribadian, Psikolinguistik, Sosiolinguistik, Ketrampilan Berbahasa non-fiksional. Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Analisis Wacana
DWI BAMBANG PUTUT SETIYADI, lahir di Klaten 12 April 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1985. Pendidikan S2 Prodi Linguistik Deskriptif, UNS Surakarta. Pendidikan S3 pada Prodi Linguistik, FIB, Universitas Gadjah Mada, tahun 2011. Tahun 1984-1987 bekerja sebagai guru tetap pada SPG dan SMA Tri Dharma Surakarta, GTT pada MAN Karanganyar dan SMA Al-Islam 2 Surakarta. Tahun 1987 diangkat sebagai DTY IKIP YP Klaten dan tahun 1989 diterima sebagai Dosen Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dpk pada IKIP YP Klaten (Universitas Widya Dharma Klaten). Mengampu mata kuliah linguistik pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; FKIP dan pada Prodi Magister Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Unwidha Klaten. Buku yang ditulis: Teori
Linguistik: Fonologi (2010) dan Teori Linguistik: Morfologi (2011), Kajian Wacana Tembang Macapat (2012); Analisis Wacana (2013); Baud Basa Jawa untuk SMP (2015; Baud Basa Jawa untuk SMA/SMK (2015).
ENDAH ANDAYANI lahir di Blitar 06 Agustus 1968. Kualifikasi Akademik dilaksanakan S1 di IKIP Malang, Program Studi Pendidikan Dunia Usaha dan lulus pada tahun 1992. Magister Manajemen ditempuh di Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2004. Sedangkan Doktor Pendidikan Ekonomi di tempuh di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang diselesaikan pada Tahun 2013. Sebagai Dosen yang diperkerjakan Kopertis Wilayah VII sejak tahun 1993 diperbantukan di Universitas Kanjuruhan Malang sampai dengan sekarang. Memiliki pengalaman mengajar selama 27 Tahun dan telah memiliki sertifikasi profesi pada kepakaran Pendidikan Ekonomi. Untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, maka telah melakukan berbagai pelatihan mulai dari pekerti sampai dengan Applied Approach yang diselenggarakan LLDIKTI 7. Selain itu pelatihan dan workshop terkait kurikulum nasional, media pembelajaran, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, peningkatan keprofesionalan pendidik, dan penelitian
New Normal, Kajian Multidisiplin | 571
secara rutin telah diikuti. Beberapa tugas yang telah dijalani dari pelatihan tersebut adalah menjadi instruktur nasional (IN) kurikulum K-13, menjadi Tim PPG, Tim analisis dan reviewr soal PPG dari PPPPTK IPS, reviewer nasional bidang penelitian di bawah naungan Ristekdikti, serta narasumber pada Ulang Tahun PGRI dan narasumber berbagai konferesi ilmiah, dan menjadi dewan Pendidikan di SMK. Hibah yang pernah diperoleh seperti: Hibah Kurikulum sebanyak 2 kali dari Belmawa, Hibah Pendidikan karakter dari Puslitjakdikbud, hibah penelitian nasional dan desentralisasi dari Ristekdikti, Hibah pengabdian masyarakat dari Ristekdikti, dan Hibah penelitian dan pengabdian dari DIPA LPPM Unikama.
ENDANG SUNGKAWATI, lulusan dari SMA Negeri Blitar, meneruskan pendidikan sarjana di IKIP Negeri Malang lulus tahun 1990, pendidikan magister diselesaikan di Universitas Brawijaya tahun 1997, dan tahun 2014 menyelesaikan pendidikan doktor bidang Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Aktifitas lain selain sebagai dosen, adalah sebagai asessor sertifikasi guru (mulai tahun 2006), asessor BNSP bidang kewirausahaan (mulai tahun 2013), sebagai asessor Calon Kepala Sekolah (mulai tahun 2015). Selain itu juga aktif mengelola jurnal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai reviewer di beberapa jurnal ekonomi yang tergabung dalam ALJEB. Mulai tahun 2014 aktif sebagai peneliti dan pengabdian masyarakat di bidang manajemen koperasi., dan setiap tahun mempuplikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, maupun internasional. Buku yang telah diterbitkan yaitu “Sistem Manajemen Koperasi”, “Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil” dan “Manfaat Koperasi Indonesia”. Ketiganya sudah Ber ISBN dan ber HKI. Pada saat ini sedang menulis tentang Modul Kewirausahaan sebagai pegangan mahasiswa.
ENY DYAH YUNIWATI, Dosen di Univ Wisnuwardhana Malang. Menjabat Ketua LPPM, dan telah menghasilkan karya di bidang Pertanian, khususnya Konservasi Lahan dan Lingkungan. Bernagai Penelitian dan Pengabdian telah di lakukan, dan aktif sebagai Reviewer Penelitian Ristekdikti, Reviewer Pengabdian Masyarakat Internal Ristek Dikti. Ketua Forum Layanan Ipstek bagi Masyarakat (Pengabdian Dosen) Flipmas Legowo Jawa Timur, Reviewer Kawasan Ekonomi Masyarakat, (KEM) Flipmas Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina Indonesia. Beberapa Paten Sederhana HKI dan Hak Cipta Buku telah diraihnya, 15 HKI lain telah diraih, a.l. Hak Cipta Buku, Hak
572 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Cipta Artikel dan HKI Poster. Sejak tahun 2017, karyanya telah muncul di Jurnal Internasional Bereputasi dan terindeks Scopus. Sebagai peng-abdi masyarakat, aktif dalam program pengembangan wilayah di Jombang, Pacitan, dan Sukapura Probolinggo, dan pendampingan ber-basis Pemberdayaan Masyarakat (Community Development). Beberapa buku monograf, telah di hasilkan, antara lain Teknologi Biochar untuk Pertanian berkelanjutan, Desa Wisata Petik Jambu Gondangmanis, Lim-bah apel untuk Hidroponik, email : [email protected]
ERITA YULIASESTI DIAH SARI, bergabung di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai dosen sejak tahun 1996 dan melakukan berbagai aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pernah berkecimpung dalam struktur Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan selama hampir 15 tahun. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan S3 pada Program Doktor Psikologi Universitas Padjadjaran. Publikasi yang dihasilkan berupa buku, artikel jurnal, proseding, dan aktif mengikuti seminar serta konferensi di berbagai tempat. Bidang minat kajian psikologi yang ditekuni adalah Psikologi Organisasi serta kajian tentang tes psikologi. Selain melak-sanakan tugas sebagai dosen, juga aktif sebagai asesor kompetensi di salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi di Yogyakarta. Alamat email yang dapat dihubungi [email protected].
FADJAR KURNIA HARTATI, staf pengajar di Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Dr. Soetomo Surabaya sejak tahun 1995 sampai sekarang, dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Penulis lahir di Surabaya pada tanggal 11 Nopember 1966. Penulis menempuh jenjang Pendidikan pada Jurusan Teknologi Pertanian mulai S1 di Universitas Jember (1986-1990), S2 (1999-2021) hingga S3 (2013-2017) di Universitas Brawijaya Malang. Penulis pernah mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi pada tahun 2018 dan 2019. Adapun pengalaman mengajar pada mata kuliah Pengenalan Industri Pangan, Kimia Dasar, Kimia Lanjutan, Kimia Pangan, Pangan Fungsional, Evaluasi Nilai Gizi, Kimia Analitik dan Analisa Pangan. Pengalaman lainnya adalah sebagai Sekretaris Pusat Pengelola Jurnal; Koordinator Pusat Percepatan Publikasi Ilmiah; Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM); sebagai Editor in Chief pada jurnal bidang Teknologi Pangan: Food Science and Technology Journal (terakreditasi Sinta 3); Reviewer Nasional Bidang Pengabdian Pada Masyarakat
New Normal, Kajian Multidisiplin | 573
FATHUR ROHMAN, guru Biologi di SMP Negeri 9 Pasuruan. S1 diperoleh dari IKIP Surabaya (Universitas Negeri Surabaya) konsentrasi pendidikan Biologi. S2 dari Universitas Adi Buana Surabaya konsentrasi Teknologi Pendidikan. Buku yang pernah di tulis “Manajemen Kelas Berbasis Multiple Intelligence” (2015).
HARUN AHMAD, dilahirkan di sebuah pulau kecil nun jauh di ujung Timur Halmahera Selatan Maluku Utara yang hanya bisa diakses dengan kapal laut, tepatnya Desa Kida Pulau Tameti, 22 Juli 1960. Menamatkan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, 1988. Menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Malang, 2008. Merampungkan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. Selain mengajar, aktif terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana Hibah dari Dikti. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian tersebut dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional antara lain PARADIGMA Jurnal Ilmiah Pendidikan Teori dan Penelitian, Journal of Humanities and Social Science, Volume 22, Issue 8, Ver. VI (August. 2017) PP 01-09, Journal of Studies in Education, Vol. 7, No. 3, August 2017. Mengikuti VIRTUAL CONFERENCE PROGRAM, 7th International Conference on Community Development in the ASEAN (ICCD 2020), July 18, 2020, dengan judul artikel “Makayaklo Cultural Knowledge in the Islands Farmers’ Survival in Kida Village, Tameti Island, North Maluku: Hermeneutics-Phenomenology Perspective of Paul Ricoeur”. Saat ini menjabat Ketua Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IKIP Budi Utomo Malang.
HENI SUKRISNO lahir pada tanggal 10 Desember 1961, di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, pekerjaan saya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tempat tinggal saya di Jalan barata Jaya XX Nomor 85 Surabaya. Adapun perjalanan pendidikan saya untuk sarjana Pendidikan Matematika S-1 diperoleh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 1986, kemudian memperoleh gelar Magister Pendidikan Matematika S-2 dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang tahun 1996. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Negeri Malang pada tahun 2006 dan memperoleh gelar doktor Manajemen Pendidikan pada tahun 2009. Adapun pengambilan pada Program Studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap pengelolaan pembelajaran
574 | New Normal, Kajian Multidisiplin
matematika yang lebih baik. Selain sebagai dosen saya juga mendapat-kan tugas tambahan sebagai ketua Badan Penjaminan mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya dapat dihubungi melalui WA atau nomor telpon 081335644940, email: [email protected].
KHOIRIYAH, dosen bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. S1 diperoleh dari IAIN Malang jurusan Tadris Bahasa Inggris, S2 diperoleh dari Universitas Negeri Malang konsentrasi bidang pengajaran bahasa Inggris. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor di Universitas Negeri Malang konsentrasi bidang pengajaran bahasa Inggris. Minat penelitianya meliputi: pengembangan profesi guru, pengajaran bahasa Inggris, merancang pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar. Buku yang pernah di tulis: “Manajemen Kelas Berbasis Multiple Intelligence” (2015). Artikel “Utilizing Project-based Learning to Raise Students’ Speaking Ability” (2015). Buku ajar bahasa Inggris: “General English for Practice” (2019). Artikel yang dimuat di Journal of International Students: “Exploring the Emotions of Single International Students in Hong Kong Facing the COVID-19 Pandemic” (2020). Mengikuti program pertukaran School administrator di Chicago,USA tahun 2006.
LILI DAHLIANI, lahir di Padang, 57 tahun yang lalu., tepatnya tanggal 25 Juli 1963. Penulis menamatkan pendidikan sarjana, pasca sarjana dan doktoralnya di fakultas ilmu-ilmu pertanian, di Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis pernah memperoleh pelatihan manajemen perkebunan mulai dari pelatihan bagi calon manajer afdeling sampai jabatan calon direksi perusahaan perkebunan. Mulai bekerja pada tahun 1989 di perusahaan swasta yang bergerak dalam reseach marketing dan menjadi dosen mulai tahun 1990. Selain berkarya sebagai dosen tetap di Program studi Teknologi dan Manjemen Perkebunan di Sekolah Vokasi IPB, Penulis adalah asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Vokasi IPB dan menjabat sebagai Manager sertifikasi di LSP tersebut yang tercatat sebagai anggota tim perumus penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang tanaman perke-bunan. Kiprah Penulis lainnya adalah Pembina Himpunan Mahasiswa Vokasi Pertanian IPB, pemerhati agrowisata perkebunan, menulis opini di beberapa media perkebunan.
New Normal, Kajian Multidisiplin | 575
LITA TYESTA ADDY LISTYA WARDHANI lahir di Purwokerto, 26 September 1960. Lulus dari Universitas Diponegoro sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1984, sebagai Magister Hukum pada tahun 1996 dan gelar sebagai Doktor Ilmu Hukum diraihnya pada tahun 2013 dengan disertasi berjudul “Menata Ulang Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Menuju Negara Hukum Demokratis”. Sejak tahun 1985, telah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia Dari UU Nomor 10 Tahun 2004 ke UU Nomor 12 Tahun 2011 Studi Kasus Peraturan KPU di Indonesia serta Perda Berbasis Muatan Agama: Problematika, Pembinaan dan Pengawasan. Sebagai anggota AMCA, telah mengikuti International Conference on Community Development pada tahun 2018 di Filipina, tahun 2019 di Brunei Darussalam dan tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring
NURUL ZURIAH, lahir di Trenggalek, 12 Juli 1966, anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan suami-istri Bapak H. Sukidi Al Sochib (alm) dan Ibu Hj. Siti Roesmini,. saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap kopertis Wilayah V I I D P K di Jurusan Civic Hukum/PPKn FKIP UMM. Jabatan Fungsional akademik lektor kepala dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Metodologi Penelitian. Selepas SMU di Trenggalek diterima melalui jalur PMDK sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Pendidikan Moral Pancasila & Kewarganegaraan IKIP Malang dan lulus pada tahun 1990. Melalui jalur Tunjangan Ikatan Dinas ia diterima sebagai dosen tetap Kopertis V I I DPK di Jurusan Civic Hukum/PKn-FKIP Universitas Muhammadiyah Malang sampai sekarang. S2 Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1996, Doktor Pendidikan Kewarganegaraannya tahun 2011 dengan predikat Cumlaude. Bidang kepakarannya pada Pendidikan Kewrganegaraan, Pembelajaran dan Karakter ditekuninya dengan menghasilkan beberapa karya monumental. Beberapa buku telah dihasilkan sebagai karya akademiknya. Pernah mendapatkan 2 kali hibah penulisan buku teks dari DP2M - DIKTI Depdiknas tahun 2000 dengan judul "Action Reasearch Teori dan Aplikasinya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2008, dan Karya Satya XX Tahun 2018.. Penghargaan Peneliti Penyaji Terbaik dalam Seminar Hasil Multi Tahun Anggaran 2008. dan Finalis Dosen berprestasi tingkat Nasional tahun 2013, selain itu sudah menerbitkan 13 buku.
576 | New Normal, Kajian Multidisiplin
MOCHAMAD RIDWAN, lahir di Malang Jawa Timur tanggal 10 Juli 1961, Agama: Islam. Pendidikan S1 ditempuh tahun 1981 s/d 1986 di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang pada Prodi Sosial Ekonomi Pertanian. Tahun 2008 telah menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1988 bekerja sebagai dosen (PNS) di Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Profesi sebagai dosen diabadikan pada semua program pendidikan yang ada yaitu S1, S2, dan S3. Berbagai mata kuliah yang diampu adalah Ekonomi Pembangunan, Teori Ekonomi Makro dan Mikro, ESDA/Lingkungan, ESDM, dll. Menulis buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal berskala nasional dan internasional, seperti: Attractive Ecotourism, Environmental Management, Poverty, and Social Capital Quality (2018); Model Pengelolaan Sumberdaya Alam Kelautan dengan Pendekatan Sosial Ekonomi (2019); dan lain-lain. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan keilmuan seperti: ISEI, AMCA, dan lain-lain
MUNAWIR PASARIBU. Lahir di Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 1983, Pengajar di Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara semenjak tahun 2008. Di UMSU mempunyai Status Dosen tetap dengan Nomor Induk Dosen Nasional bernomor : 0116078305 dengan kepangkatan Lektor III/d. Sekarang tinggal di Jalan Bajak V Villa Mutiara I Nomor J 5 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan ditempuh SD Muhammadiyah Barus Mudik tahun (1992–1997). Madra-sah Tsanawiyah Negeri Barus ( 1997–1999) Madrasah Aliyah Negeri Barus (1999–2001). S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam (2001 – 2005). S2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Pendidikan Islam (2006–2009). S3 Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Pendi-dikan Agama Islam (2016 -2019).
NURCHOLIS SUNUYEKO, lahir di Blitar, 22 Desember 1961. Saat ini menjabat Rektor di IKIP Budi Utomo Malang. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Malang, tamat 1985. Sejak 1989 menjadi dosen PNS LLDIKTI VII diperbantukan di IKIP Budi Utomo Malang. Menamatkan pendidikan S2 Program Studi Sosiologi konsentrasi Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. Menyelesaikan pendidikan S3 Program Studi Ilmu Sosial
New Normal, Kajian Multidisiplin | 577
Universitas Merdeka Malang, 2016. Hibah penelitian yang dilaksanakan di antaranya “Optimalisasi Pengimplementasian Kurikulum 2013 melalui Pendampingan Guru Sekolah Dasar di Kota Malang” pendanaan Kemeristekdikti melalui Penelitian Desentralisasi 2014. Hasil penelitian ini dimuat di jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Tahun 25 Nomor 1 Mei 2016. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul “Social Interactions of Student Sojourners: A Study of Adaptation and Acculturation of Flobamora Students at a Multi-Ethnic Private University of Malang City” dan dimuat di jurnal IOSR Journal of Research & Method in Education Volume 7 Issue 6 Page 1 2016 2017/11. Aktif mengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi dengan spesialisasi matakuliah Sosiologi dan penguji di Pascasarjana Program Studi Pendidikan Olahraga IKIP Budi Utomo Malang.
NURUL QOMARIAH, Sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember sejak 2006 sampai dengan sekarang. Pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat periode 2015-2019 di Universitas Muhammadiyah Jember, dan berhasil membawa prestasi untuk Kinerja Penelitian Universitas Muhammadiyah Jember masuk Klaster Utama. Beberapa judul buku sudah ditulis diantaranya: Nilai-nilai Islam di Perguruan Tinggi tahun 2012 yang merupakan buku Monograf. Menulis buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2015 dengan beberapa kolega. Tahun 2016 menulis buku Marketing Adactaive Strategy yang merupakan buku yang mengkaji masalah strategi pemasaran dengan pendekatan Marketing Mix. Pendidikan sarjana manajemen diselesaikan di Universitas Jember tahun 1992, Magister Manajemen juga di Universitas Jember tahun 2006 dan Doktor bidang manajemen diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang tahun 2012.
PIETER SAHERTIAN, adalah tenaga pengajar pada Universitas Kanjuruhan Malang. Menyelesaikan studi S-1 di IKIP Malang, sedangkan pendidikan S-2 serta doktoralnya diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang. Menekuni bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kekhususan kajian bidang “kepemimpinan”. Oleh karena itu riset-riset yang dilakukan sejak tahun 2008 sampai sekarang adalah dalam bidang kepemimpinan. Selama tiga periode hibah penelitian baik mono maupun multi tahun didapatkan dari Kemen-dikbud maupun Kemenristekdikti untuk penelitian dalam bidang kepemimpinan. Penulis juga aktif mengajar, menulis, meneliti, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian baik di jurnal maupun
578 | New Normal, Kajian Multidisiplin
konferensi pada level nasional maupun internasional dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi maupun Kepemimpinan
ROCHSUN, lahir di Banyuwangi pada 26 Juli 1964. Sarjana pendidikan matematika di UMM. Magister di UNAIR Surabaya dengan minat studi Biostatistika, dan Doktor UMM minat studi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah menjadi dosen Yayasan di IKIP BU SK. Nomor : 36/1-a/IX/1989, kemudian sejak tahun 1991 doen DPK pada IKIP Budi Utomo Malang SK. Capeg Nomor: 1122/C.1/E/1991 NIP 131947777. Jabatan Lektor Kepala 1 Agustus 2004 NIP 196407261991031003 dan sejak 1 Oktober 2007 menjadi pembina golongan ruang IV.a. Mengampu Mata Kuliah Statistika, dan akhir-akhir ini dipercaya mengajar mata kuliah Kebudiutamaan. Hasil Karya Ilmiah Rochsun (1) pada tahun 2012 menulis di jurnal Nasional berjudul Studi Tanggapan masyarakat terhadap upacara adat Barong Ider Bumi desa Kemiren Banyuwangi dimuat oleh jurnal nasional Humaniora 9(1), 6-13. 2012. (2) Pada tahun 2014, menulis hasil penelitian hibah bersaing berjudul Spirit Budaya Using: Studi Fenomenologi Upacara Adat Ider Bumi dimuat pada jurnal Humaniora Volume 11 Nomor 2 Desember 2014. (3) Pada 2017 menulis jurnal hasil penelitian hibah bersaing pada jurnal internsional IQSR Jounal of Research & Method in Education 7 (5). 13. 2017 berjudul Edugame Develompment Character For Non Mathematic Students At Statistic Subject. (5) Pada tahun 2018 menulis pada Jurnal Paradigma 24(2),9.18.2018 berjudul Musik Tradional Jawa Janengan Yang Terlupakan (A Forgotten Javanese Traditional Musinc Janengan). (6) Pada tahun 2019 Peroleh HAKI nasional nomor sertifikat EC00201992475 Judul Spirit Barong Ider Bumi Masyarakat Using Desa Kemiren Banyuwangi. (7) Pada Februari 2020, menulis pada jurnal PJM Volume 6. Nomor 1. Februari 2020, Halaman 53-57 E.ISSN: 2656-4564 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Hand Quick Pada Materi Operasi Bilangan Bulat Siswa Kelas VII. (8) Pada Tahun 2020 menulis buku terbitan Bildung kerjasama dengan AMCA ISBN:978-7148-63-0 berjudul Spirit Aclak, Bingkak dan Ladak: Interaksi Simbolik Upacara Adat Barong Ider Bumi. Menguak Sisi dalam Masyarakat dan Budaya Using Kontemporer.
PREMBAYUN MIJI LESTARI, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang pernah diampu diantaranya: Sosiolinguistik, Analisis Wacana, Pragmatik, Menulis Kreatif, Psikolinguistik, Metodologi Penelitian Linguistik, dan Seminar Linguistik. Pengalaman penelitian dan
New Normal, Kajian Multidisiplin | 579
pengabdian, selalu aktif terlibat baik sebagai ketua maupun anggota untuk penelitian di tingkat UNNES maupun DRPM Dikti. Penulis aktif menulis puisi, geguritan, artikel jurnal nasional/ internasional, artikel seminar, dan bookchapter. Selain itu penulis terlibat menjadi reviewer di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan WOS: Widyaparwa (Balai Bahasa Yogyakarta), Register Journal (IAIN Salatiga), dan Inchief Editor Sutasoma UNNES (Sinta 4). Penulis sering mengisi seminar, pelatihan kepenulisan atau klinik manuskrip di berbagai forum. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Mendeley Advisor Indonesia atau menjadi instruktur aplikasi referensi penulisan ilmiah mendeley
RETNO PURNAMA IRAWATI, lahir di Surakarta, 25 Juli 1978. Mengajar di prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang diampu: Psiko-linguistik, Pengantar Linguistik Umum, Metode Penelitian Bahasa Arab, dan Statistika. Selain mengajar, penulis banyak melakukan penelitian di bidang pendidikan, sastra, dan linguistik, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berhasil didanai DIKTI: Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berkarakter dan Berbudaya Bagi Siswa SD Melalui Sastra Anak; Pemaknaan Nilai-Nilai Karakter dan Budaya Menurut Sudut Pandang Anak-Anak Pada Lagu Anak dan Lagu Dolanan Anak Indonesia; dan Pengembangan Ensiklopedia Bahasa Jawa Berbasis Kearifan Lokal dan Konservasi Budaya sebagai Buku Pengayaan Bagi Masyarakat Jawa Tengah (2017-2018). Buku yang dihasilkan antara lain: Pengantar Memahami Sastra (2009 ditulis bersama suami, Siminto, S.Pd., M.Hum); Mengenal Sejarah Sastra Arab (2012); Pengantar Memahami Linguistik
(2013); dan Pembelajaran Menulis Cerpen (2016)
RIZKA HARFIANI, lahir di Jakarta, tanggal 3 Nopember 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di USU, Medan (1993-1999), dan S1 PAI di STAIS, Medan (2004-2009), kemudian melanjutkan S2 Psikologi Pendidikan di UMA, Medan (2010-2012), serta S3 PAI di UMM, Malang, Jawa Timur (2017-2020). Kini mengabdi sebagai dosen di UMSU, Medan. Karya: Buku Perencanaan Pembelajaran, Buku Kreativitas Raudhatul Athfal, Buku Inclusive Education Program Implementation of Early Children, Buku Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Inklusif Pada Anak Usia Dini, serta artikel-artikel lainnya yang telah terpublish. email [email protected]
580 | New Normal, Kajian Multidisiplin
SUPRIATNOKO. Lahir di Cirebon, dari pasangan Bapak Marsam Soelosso asal Jombang dan Ibu Hj. Satimah asal Cirebon. Sekolah TK sampai SMA di kota kelahirannya dan hijrah ke Jakarta pada tahun 1981 untuk melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Negeri Jakarta—sekarang bernama Universitas Negeri Jakarta—lulus tahun 1986. Di tahun yang sama diterima menjadi dosen di Politeknik Universitas Indonesia dan sekarang bernama Politeknik Negeri Jakarta. Mendapat pendidikan khusus sebagai dosen politeknik selama 10 bulan di PEDC Bandung. Awal penugasannya di tahun akademik 1987/1988 sebagai dosen mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis di Jurusan Akuntansi. Lulus S2 Program Studi Ilmu Susastra FIB UI sebagai Magister Ilmu Susastra di tahun 1999. Dari perolehan gelar ini, dia menekuni kepakarannya di bidang Sosiologi Sastra. Tahun 2015 mendapatkan gelar Doktor Ilmu Linguistik dengan kepakaran di bidang Sosiolinguistik dan Geografi Linguistik. Aktif mengikuti berbagai Seminar, konferensi, dan pelatihan (nasional dan Internasional) baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara. Tulisannya pun pada keempat bidang kepakaran itu. Di samping aktifitas keilmuan, dia juga mendapat amanah untuk menduduki berbagai jabatan di tempat mengabdinya, dari jabatan paling rendah sampai yang dianggap bergengsi dimulai sebagai Penangung Jawab Laboratorium Bahasa (1992-1994), Koordinator Bidang Keahlian Bahasa Inggris (1994-1999), Kepala Program Pendidikan Aplikasi Bisnis (2001-2004), Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2004-2008), sebagai Staf Ahli Pembantu Direktur Bidang Kerjasama(2014-2016), sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Bahasa (2016-2017), sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi (2017-2019), sebagai Sekretaris Program Pascasarjana (2019-2020), dan sejak 2020 menjabat sebagai Kepala Program Pascasarjana, dan mengajar Mata Kuliah Seminar di Program Studi Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur. Aktivitas lainnya adalah menjadi reviewer di beberapa Jurnal Sosial Humaniora, anggota HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia), MLI (Masyarakat Linguistik Indonesia), dan AMCA (Association of Muslim Community in ASEAN).
SUDJIWANATI, Kepakaran di bidang Psikologi Klinis, melayani beribu-ribu pasien gangguan kejiwaan di RSJ dan praktek Pribadi, mendirikan Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Aditya. Nama akrab panggilan Ibu Atik, Sudjiwanati lahir di Malang, suami seorang Doktor Psikiater TNI AD, dua orang anak sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dan Dokter Spesialis Anestesi. Studi S1
New Normal, Kajian Multidisiplin | 581
Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, S2 Bimbingan Konseling Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, dan S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Sebagai Psikolog Klinis di RSJ Lawang selama 35 tahun, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang, Kepala Laboratorium Psikologi, Chief Editor Jurnal Psikovidya dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Mengajar MK, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Konsumen, Psikologi Eksperimen, Psikoterapi, Teknik Konseling, Psikodiagnostika, Observasi. Pengalaman organisasi, Ketua Cabang HIMPSI Malang, Pengurus HIMPSI Wilayah Jatim, Pengurus HIMPSI Cabang Malang, PDSKJI, Flipmas Legowo, ADRI, AMCA, HIMPSI, IPK yang ditekuni saat ini.
SUTAWI, lahir di Pati pada 22 April 1965, menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan UGM (1989), program magister di Program Studi Ekonomi Pertanian Program Pascasarjana UGM (1996), dan pendidikan doktor di Program Doktor Ilmu Ternak Fakultas Peternakan UB (2012). Sejak tahun 1990 menjadi dosen di Fakultas Peternakan UMM, yang sekarang menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan UMM. Pernah menjabat Dekan Fakultas Peternakan UMM (1996-1998) dan Ketua Program Studi Magister Agribisnis Program Pascasarjana UMM (2006-2008). Selain menulis dua buku Manajemen Agribisnis (Bayu Media, 2002) dan Kapita Selekta Agribisnis Peternakan (2007), juga telah memublikasikan 500-an artikel ilmiah populer di koran dan majalah seperti: Poultry Indonesia, Trobos, Infovet, Sinar Tani, Malang Post, Bhirawa, Kompas, dan Jawa Pos, dan beberapa artikel ilmiah di jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pernah beberapa kali menjadi juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Komunikasi dapat disampaikan melalui email: [email protected]
TRI REJEKI ANDAYANI, Sosok yang akrab dipanggil Menik ini lahir di Boyolali dengan nama lengkap Tri Rejeki Andayani. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pendidikan pascasarjana S2 dan S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, lulus Doktor dengan predikat cumlaude tahun 2016. Sejak akhir 2009 menjadi dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Surakarta, setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai wartawan di Suara Merdeka Semarang (1997), serta menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (Undip), Semarang selama 12 tahun (1998 s.d. 2009). Aktif menjadi peergroup di Pusat Studi Difabilitas (PSD) dan
582 | New Normal, Kajian Multidisiplin
Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) LPPM UNS, serta menjadi Ketua RG Indigenous Psychologi Prodi Psikologi FK UNS. Organisasi yang diikuti a.l. menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Psikologi Islam (API), Asosiasi Psikologi Indigenos dan Kultural (APIK), Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia (APKI), Asosiasi Psikometri Indonesia (Apsimetri), Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat (FLipMAS), Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA), dan menjadi Pengurus Ikatan Psikologi Sosial (IPS) HIMPSI. Minatnya pada relasi sosial dan pengukuran yang berbasis Indigenous Psychology dituangkannya dalam berbagai aktivitas, baik sebagai penulis dan reviewer jurnal nasional maupun sebagai peserta dan pembicara dalam berbagai pelatihan dan forum ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain publikasi di jurnal ilmiah, beberapa karyanya juga dipublikasikan di media massa (surat kabar), proceeding dan buku. Korespondensi: [email protected].
UMI FARIHAH dilahirkan di Lamongan 01 Juli 1968. Ia menyelesaikan studi jenjang sarjana pada Program Studi Tadris Matematika IAIN Malang pada tahun 1990, jenjang magister pada Program Studi Manajemen STIE ABI Surabaya pada tahun 2002 dan pada Program Studi Pendidikan Matematika UMM pada tahun 2015. Studi jenjang doktor Manajemen Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Malaysia diselesaikannya pada tahun 2012. Saat ini ia berkedudukan sebagai dosen tetap di IAIN Jember, dengan jabatan sebagai Ketua Prodi Tadris Biologi. Selain mengajar, meneliti, dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ia juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah. Beberapa artikel yang telah dipublikasikanya antara lain: 1) Students’ Thinking Preferences in Solving Mathematics Problems Based on Learning Style: a Comparison of Paper Pencil and Geogebra (2018), 2) The Synergy of Students’ Use of Paper Pencil Technique and Geogebra in Solving Analytical Geometry Problems (2019), 3) Student Modelling in Solving The Polynomial Functions Problems using Geogebra Approach (2019)
ZAINAL ABIDIN ACHMAD, lahir di Pacitan, 19 Mei 1973. Lulus S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga (1998). Lulus S2 Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga (2001). Lulus S2 Bilingual Education Rangsit University Thailand (2006). Lulus S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga (2020). Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penerima: Beasiswa Djarum (S1 Unair), URGE Batch-V Scholarship (S2 Unair), Arthit Ourairat Scholarship (S2
New Normal, Kajian Multidisiplin | 583
RSU Thailand), dan BPPDN-PTNB (S3 Unair). Ia memiliki pengalaman mengajar jurnalistik pers, hukum media massa, komunikasi politik, sosiologi komunikasi, media relations, dan etnografi virtual. Ia menghasilkan buku-HKI: Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers Indonesia, English for Specific Purpose, Ayo Membuat Surat Kabar, Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2017, dan Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018. Ia memiliki pengalaman kerja advokasi dan community development bersama Kementerian, NGO dalam/luar negeri, dan badan dunia (Kementerian PUPR, BAPPENAS, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenag, LP3ES, PUPUK, REDI, World Bank, USAID, AusAID, The Asia Foundation, dan UNDP.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































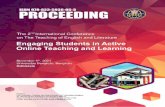








![[biodiv] Submission Acknowledgement - UNIB Scholar ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63240a99117b4414ec0c9818/biodiv-submission-acknowledgement-unib-scholar-.jpg)