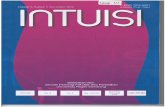Jurnal Cendekia UGM
Transcript of Jurnal Cendekia UGM
N
o. 1
Vo
lum
e 1
De
sem
be
r-Ju
ni 2
01
3
Jurn
al
Ce
nd
ek
ia
P
en
eli
tia
n d
an
Ka
jia
n I
nte
rdis
ipli
ne
r M
ah
asi
swa
Jurnal Cendekia merupakan jurnal yang memuat laporan
penelitian, artikel ilmiah, sinopsis buku serta catatan
lapangan yang dikaji berdasarkan pendekatan
interdisipliner oleh mahasiswa. Jurnal Cendekia
diharapkan dapat berperan sebagai media berbagi
pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai penelitian
berbasis interdisipliner yang efektif dan inovatif. Jurnal
Cendekia adalah jurnal berkala yang terbit dua kali setiap
tahun periode Juli dan Desember. Hak cipta @Gama
Cendekia Universitas Gadjah Mada. Dilarang
menggandakan isi tulisan dalam bentuk apapun selain
dengan ijin penerbit. Alamat redaksi: Gelanggang
Mahasiswa Jl. Pancasila No. 1 Bulaksumur Yogyakarta.
Website: http//gc.ukm.ugm.ac.id
Pemimpin Redaksi
Azizatul Ulfa
Dewan Redaksi
Denis Febta Dianingratri
Wulan Fatimah Rohman
Lusi Nur Rahmawati
Mulia Ela
Redaktur Pelaksana
Lilis Sulistyaningsih
Mukhammad Faisol Amir
Yuni Arum Sari
Ridwan
Distribusi
Abdul Afif Almuflih
Mitra Bestari
Rachman Sudiyo, M.T,, Ph.D (Universitas Gadjah Mada)
Waziz Wildan, M.T (Universitas Gadjah Mada)
Dr. Murwantoko (Universitas Gadjah Mada)
Moh. Abdul Hakim, MA (Universitas Sebelas Maret)
Alam Firmansyah M.Sc (Universitas Achmad Dahlan)
Daftar Isi
Isolasi α-pinene pada menara distilasi bahan isian untuk mengurangi laju
deforastasi hutan Indonesia 1- 8
Ibrahim Ats-Tsauri, Rahmat Alfathi, Erlina Nur Arifani
Facile Hydrothermal Synthesis of Various Nanostructured 9- 18
Erni Astuti, Yateman Arryanto, Indriana Kartini
Komanglawit (kompor berbahan bakar cangkang kelapa sawit) sebagai
solusi alternatif pengganti kompor minyak 19-28
Lestari Wevriandini
Animal waste integrated processing system (Aniwasin Prosys): Energi
ramah lingkungan dalam upaya peningkatan pendapatan peternak Dusun
Kalipucang, Kasihan-Bantul, Yogyakarta 29-36
M. Faishol Amir, Ershalat Tahta Nabhanudin, Dwi Abdul Mufi
“AISOC” Animal Incubator with Automatic Colostrum System 36-40
Dwi Kristanto, Fivien Fidiyanti, Saprindo Harun Prabantara,
Agus Wigiardi, Birrul Qodriyyah, Irkham Widiyono
“Curcumax” Reagen Praktis Penguji Kandungan Boraks Pada Bakso 41-45
Muhammad Arifin, Aris Eka Wijaya, Andyta Septi K,
Rina Irmayanti L, Erna Dwi Astuti
Peningkatan Fertilitas Telur Persilangan Ayam Isa brown
dan Ayam Bangkok Dengan Metode Inseminasi Buatan 46-58
Rizki F, Fivien Fidiyanti, Melisa Ekaningrum, Triatun, Dani A.S
“Balet” Belalang Nugget Berprotein Tinggi, Sebagai Alternatif
Pemenuhan Protein Hewani Masyarakat 59-63
Ridho Andika Putra, Anti Ahsati, Azizatul Ulfa, Muhammad
Rizki Adrian, Muhammad Fikri
Analisis Potensi Kombinasi Stimulasi Akupuntur dengan Bee Venom pada
Titik Akupuntur ST36 Sebagai Pendekatan Preventif Komplikasi Vaskuler
Pada Diabetes Mellitus Tipe II 64-75
Gamal
Benalu Teh (Scrurrula atropurpurea) Sebagai Herbal Alternatif Antibakteri
untuk Pengobatan Infeksi Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) 76-83
Novra Arya Sansi, Siti Isrina Oktavia Salasia
Seleksi Populasi F2 Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) Berdasarkan
Sifat Buah 84-99
Imam Wibisono, Taryono, Nasrullah
Peta Flash Interaktif Sebagai Penunjang Pariwisata Pulau Maratua 100-110
Agung Widcha Aulia Rachman
Nilai Filosofi Upacara Adat Mappaci pada Pernikahan Suku Bugis
di Sulawesi Selatan 111-123
Nasharuddin, Wahyuddin, Irwanto, Abd. Rahman Rahim
SRAWUNG: Strategi Advokasi Masyarakat Sedulur Sikep Terhadap
Rencana Pabrik Semen 124-150
Lutfi Untung Angga Laksana
Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak Tanggal 22 Juni 2013 150-200
Ali Sulas Hidayat
ISSN: 2354-6778
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
1
ISOLASI α-pinene PADA MENARA DISTILASI BAHAN ISIAN UNTUK
MENGURANGI LAJU DEFORASTASI HUTAN INDONESIA
Ibrahim Ats-Tsauri1, Rahmat Alfathi
2, Erlina Nur Arifani
3
1Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
2Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
3Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
The objectives of this research are toproduce high purity α-pinene in a continuous two-packed-
distillation-column and also to studythe effect of operating pressure variation on MD II and feed
plate variationon MD I to the purity of α-pinene product.Turpentine is an ideal system which
does not form azeotrope so can be separated up to the purity of 100%. Isolation of α-pinene was
done ina continuous two-packed-distillation-column. The distillation process was being carried
out in vacuum pressure to prevent product damage due to high temperature decomposition.
Pressure variations shows that the increase in vacuum pressure will increase the purity of MD II
α-pinene with the range of 87.80-89.01% purity. Feed plate variationson MD I shows that the
decrease in feed plate location will reduce the purity of α-pinene with the range of 89.52-
87.10% purity.Results of ASPEN Plus 7.1 simulations indicated that the average relative error
of simulation results against experimental results for pressure variations on MD II is 0.2128%
and for feed plate variations on MD I is 0.5428%. The relative error of the simulation
experiment is small enough so that the ASPEN simulation can be used to estimate the
characteristics of the separation in the continuous distillation column.
Keywords: α-pinene, continuous vacuum distillation, turpentine
PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara yang mengalami laju deforestasi hutan tropis paling cepat di
dunia. FWI pada tahun 2001 menyebutkan bahwa laju deforestasi Indonesia adalah sekitar 6,2
juta are per tahun dan terus bertambah. Salah satu penyebab besarnya laju deforestasi ini
karena lebih dari setengah hutan di Indonesia dialokasikan untuk pengelolaan hasil hutan
berbasis produk kayu. Produk kayu adalah hasil hutan berupa kayu yang dapat dimanfaatkan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
2
langsung dalam bentuk kayu non-olahan ataupun melalui proses olahan secara mekanis seperti
kayu bulat tropis, kayu gergajian, kayu lapis, serta pulp untuk pembuatan kertas.
Upaya untuk mengurangi laju deforestasi adalah mengurangi pengelolaan hutan berbasis
produk kayu dan menggantinya menjadi pengelolaan hutan berbasis produk non-kayu. Contoh
produk hutan non-kayu adalah rotan, madu, dan resin. Indonesia memiliki hutan pinus yang
luas dan tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Pohon pinus menghasilkan getah yang
dapat diambil tanpa harus menebang pohonnya. Getah pinus bila diolah akan menghasilkan
gum dan turpentine yang dapat menjadi hasil hutan non-kayu andalan (Coppen dan Hone,
1995).
Kegunaan utama dari turpentine semula adalah sebagai solven cat, namun pada
perkembangannya menjadi bahan dasar yang sangat penting bagi industri kimia. Komponen
utama dalam turpentine, α-pinene, merupakan bahan kimia antara untuk sintesis banyak
produk fine chemical dan industri farmasi seperti parfum, aroma, dan resin politerpen
(Eggersdorfer, 1999). Selain itu α–pinene juga dapat diolah secara langsung menjadi perfume-
grade α-terpineol (Muller and Lamparsky, 1994). Agar dapat digunakan sebagai bahan kimia
antara, α–pinene perlu diisolasi agar kemurniannya tinggi (Thompson, 2000).
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh α-pinene dengan kemurnian tinggi,
mengetahui pengaruh tekanan terhadap kemurnian α-pinene pada kolom distilasi, serta
mengetahui pengaruh plat pemasukan umpan pada kolom distilasi primer terhadap kemurnian
α-pinene.
MATERI DAN METODE
Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Turpentine berupa cairan bening yang
diperoleh dari PT. Perhutani Anugerah Kimia dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 2.Komposisi Turpentine
Senyawa Kimia Fraksi Mol,%
α-Pinene 75.16
3-carene 14.82
β-Pinene 3.52
Camphene 3.5
Limonene 3
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
3
Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kolom bahan isian kontinyu yang
masing-masing dilengkapi kondenser pada bagian atas dan reboiler pada bagian bawah.
Rangkaian alat dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3.Rangkaian Alat Distilasi
Metode Penelitian
Pengambilan data dilaksanakan melalui percobaan secara kontinyu dengan skala
laboratorium. Tahapan percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Start-up MD I dan MD II sampai MD I mencapai kondisi steady state.
b. Pengumpulan distilat MDI.
c. Rekayasa kondisi operasi MD II sampai MD II mencapai kondisi steady state.
d. Variasi tekanan pada MD II.
e. Variasi feedplate pada MD I.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Distilat MD I
Kemurnian α-pinene yang diperoleh dari hasil uji tersebut berturut-turut adalah
82,03%, 82,69% dan 82,46%. Dari ketiga hasil uji MD I tersebut dihasilkan kemurnian α-
pinene yang relatif sama, sehingga kondisi operasi dengan tekanan vakum 13 in Hg dan refluks
rasio 0 dipakai untuk percobaan selanjutnya.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
4
Variasi Tekanan Operasi MD II
Hubungan refluks rasio dengan kemurnian α-pinene hasil percobaan dan simulasi
ditampilkan pada Gambar 3. Peningkatan tekanan vakum (penurunan tekanan operasi) akan
menyebabkan kenaikan kemurnian α-pinene pada distilat MD II. Semakin rendah tekanan
operasi, semakin cepat laju uap yang naik dari bagian bawah MD ke puncak MD sehingga
turpentine akan mulai menguap pada temperatur yang lebih rendah. Jika beban pemanasan
reboiler dan pemanas samping dijaga tetap, maka untuk tekanan operasi yang semakin rendah
turpentine akan semakin mudah menguap.
Gambar 3. Pengaruh Tekanan Operasi Pada MD II Terhadap Kemurnian α-Pinene
Tekanan operasi 11.9 in Hg merupakan tekanan operasi yang optimum, karena
penurunan tekanan operasi lebih lanjut tidak disertai dengan kemurnian α-pinene yang
signifikan. Kesalahan relatif rata-rata hasil penelitian terhadap hasil simulasi ASPEN untuk
variasi tekanan MD II adalah 0,2128 %. Kesalahan relatif tersebut cukup rendah sehingga
simulasi ASPEN dapat digunakan untuk memperkirakan karakteristik hasil separasi pada
menara distilasi.
Variasi feedplate MD I
Hubungan feed platedengan kemurnian α-pinene hasil percobaan dan simulasi
ditampilkan pada Gambar 4. Dapat diamati bahwa pada posisi feedplate mempengaruhi
kemurnian α-pinene yang dihasilkan pada produk. Pada posisi feedplate ke-2 kemurnian α-
pinene yang diperoleh adalah kemurnian yang optimum yaitu sebesar 0.8938.
0.8750
0.8800
0.8850
0.8900
0.8950
0.9000
12 13 14 15 16 17
Ke
mu
rnia
n α
pin
en
(X
d)
Tekanan Operasi (P), in Hg
Grafik Pengaruh Tekanan Operasi pada MD II terhadap Kemurnian α-pinene
Hasil Penelitian
Simulasi Aspen
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
5
Gambar 4. Pengaruh Refluks Rasio terhadap Kemurnian Alpha Pinene
Posisi feedplate yang komposisi cairannya relatif sama dengan komposisi cairan pada
umpan akan menghasilkan kemurnian distilat yang optimum pada kondisi operasi yang sama.
Sebabnya adalah karena setiap stage pada menara kolom distilasi mengalami kesetimbangan
uap-cair. Komponen-komponen yang ada pada stage tersebut memiliki profil kesetimbangan
tertentu di setiap stage menara distilasi. Untuk mengetahui profil kesetimbangan perlu
dilakukan perhitungan plate-to-plate. Pada penelitian ini digunakan simulasi ASPEN untuk
melakukan perhitungan plate-to-plate di setiap stage karena dapat menggambarkan profil
konsentrasi α-pinene di setiap stage MD II.
Simulasi menunjukkan bahwa posisi feedplate yang optimum merupakan posisi
feedplate ke-2 karena perbedaan komposisi antara umpan relatif sama dengan komposisi pada
plate ke-2 jika dibandingkan dengan posisi feedplate ke-3 atau feedplate ke-5.
Bila umpan dimasukkan pada posisi feedplate ke-3 atau ke-5 yang profil komposisinya
masih jauh berbeda, perbedaan profil komposisi ini akan membuat terjadinya olakan di setiap
stage menara distilasi dan tentu saja hal tersebut akan memperbesar gangguan transfer massa
sehingga kesetimbangan yang ingin dicapai tidak sempurna. Grafik profil komposisi α-pinene
di setiap plate MD I untuk variasi lokasi feed plate dapat dilihat pada Gambar 5.
0.865
0.87
0.875
0.88
0.885
0.89
0.895
0.9
2 3 4 5Kem
urn
ian
α p
inen
(X
d)
Lokasi feed plate MD I
Grafik Pengaruh Refluks Rasio terhadap Kemurnian Alpha Pinene
Hasil Penelitian
simulasi aspen
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
6
Gambar 5. Grafik Profil Komposisi α-pinene di Setiap Plate MD I pada Variasi Lokasi FeedPlate
Dari Gambar 5, dapat diamati profil komposisi α-pinene di setiap plate MD I untuk
variasi posisi feedplate masing-masing pada posisi ke-2, ke-3 dan ke-5. Dapat dilihat pula
komposisi umpan (fraksi mol α-pinene = 0,7515). Dari ketiga gambar tersebut profil komposisi
yang pergerakannya paling linear dan menghasilkan kemurnian α-pinene paling tinggi
ditunjukkan oleh umpanyang masuk pada feed plate ke-2. Hal ini menunjukkan posisi
feedplate yang optimum merupakan posisi feedplate ke-2. Sebabnya adalah karena komposisi
α-pinene umpan lebih mendekati komposisi α-pinene pada plate ke-2 daripada komposisi pada
feedplate ke-2 maupun feedplate ke-3.
Bila umpan dimasukkan pada posisi feedplate ke-2 maka gangguan transfer massa
yang terjadi di setiap stage menara distilasi menjadi lebih kecil sehingga proses kesetimbangan
di setiap plate menjadi lebih sempurna dan menghasilkan kemurnian distilat yang lebih
optimum. Tentu saja hal ini akan menghasilkan hal yang berbeda jika umpan dimasukkan pada
posisi feedplate ke-2 atau ke-3, dimana perbedaan komposisi umpan dengan komposisi plate
ke-2 ataupun plate ke-3, masih jauh berbeda. Hal ini akan membuat terjadinya olakan
komposisi di setiap stage menara distilasi dan tentu saja hal tersebut akan memperbesar
gangguan transfer massa sehingga kesetimbangan yang ingin dicapai tidak sempurna.
Galat relatif antara hasil simulasi (kondisi ideal) dengan penelitian (kondisi sebenarnya)
disebabkan oleh:
1. Tekanan operasi tidak dapat konstan sepanjang waktu.
2. Kran pengatur refluks rasio yang sulit dikontrol sehingga refluks rasio tidak bisa konstan
sepanjang waktu.
3. Aliran umpan dan distilat terus berubah-ubah pada distilasi vakum.
1
2
3
4
5
6
0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
Stag
e M
DI
Fraksi Mol α-Pinene
Grafik Profil Komposisi α-pinene di Setiap Plate MD I padaVariasi Lokasi Feed Plate
Feed Stage ke-2
Feed Stage ke-3
Feed Stage ke-5
Fraksi mol α-pinene
pada umpan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
7
4. Adanya kebocoran pada alat sehingga ada α-pinene yang hilang ke udara.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, Isolasi α-pinene dari
turpentine untuk memperoleh α-pinene kemurnian tinggi cocok dilakukan dengan dua kolom
distilasi bahan isian. Penurunan tekanan operasi atau peningkatan tekanan vakum akan sedikit
meningkatkan kemurnian α-pinene di distilat. Posisi feed plate yang optimum untuk pada
distilasi kontinyu ini terletak pada plate dengan profil konsentrasi yang sesuai dengan
konsentrasi feed, yaitu terletak pada feed plate ke-2.
Daftar Notasi
B = Aliran massa di bottom, gram
D = Aliran massa distilat, gram
F = Aliran massa di feed, gram
L = Aliran massa dari kondensor yang dikembalikan ke menara, gram
R =Refluks Rasio
Po = Tekanan uap murni
Pt = Tekanan pada menara distilasi
V = Aliran massa meninggalkan kondensor, gram
x = Fraksi mol cair
XD = Fraksi massa komponen di distilat
XF = Fraksi massa komponen pada umpan
y = Fraksi mol gas
ρ = Massa jenis, gram/cm3
DAFTAR PUSTAKA
Coppen, J.J.W., and Hone, G.A., 1995, “Non-wood forest products 2/ Gum Naval Stores:
Turpentine and Rosin from Pine Resin” , FAO, Rome.
Eggersdorfer, M, 1999, “An Ullmann‟s Encyclopedia-Industrial Organic Chemicals-Starting
Materials and Intermediates”, vol 8, Wyley-vch, Deutschland.
FWI, 2001, “Keadaan Hutan Indonesia”, Forest Watch Indonesia, Bogor.
Jajat, H dan Hansen, C.P., 2001, “Informasi Singkat Benih”, Indonesia Forest Seed Project,
Bandung.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
8
Landolt, H. and Bornstein, R., 1999, “ Vapor Pressure of Chemicals: Vapor Pressure and
Antoine Constant for Hydrocarbons, and Sulfur, Selenium, Tellurium, and Halogen
Containing Organic Compounds”, Springer Verlag, Heidelberg.
Langenheim, J. H., 2003, “Plant resins: chemistry, evolution, ecology, and ethnobotany”, pp.
306-325, Timber Press, Inc., Oregon.
Muller, F. M., and Lamparsky, D., 1994, “Perfumes: Art, Science, and Technology”, 4ed., 412,
Chapman and Hall, Glasgow.
Pocius, A. V, Dillard, D. A., and Chaudury, M. K., 2002, “The Mechanics of Adhesion”, p.
610, Elsevier Science B.V., Amsterdam.
Riegel, E. R. and Kent, J. A., 2003, “Riegel‟s Handbook of Industrial Chemistry”, 10 ed., p
237, Plenum Publishers, New York.
Santos,F.G., and Morgado, A.F., “Alfa-terpineol Production From Refined Sulphate
Turpentine”, 2nd
Mercosur Congress on Chemical Engineering.
Scheiwetzer, 1979, “Handbook of Separation Techniques for Chemical Engineers”, p. 186,
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York.
Thompson, K. L., 2000, “Arizona Chemical: Converting Papermaking and Citrus Byproducts
to Performance Chemicals and Materials”, Savannah Technology Center, Savannah.
Treybal, R., E., 1984, Mass Transfer Operation, 3ed., pp. 342-460, McGraw-Hill International
Book Company, Tokyo.
Wiyono, B., Tachibana, S., and Tinambunan D., 2006, “Chemical Composition of Indonesian
Pinus Merkusii Turpentine Oils, Gum Oleoresins, and Rosins from Sumatra and Java”,
Pakistan Journal of Biological Sciences, 9, 7-14.
Zinkel, D. F. and Russel, J., 1989, “Naval Stores: Production, Chemistry, and Utilization”,
Pulp Chemicals Association, New York.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
9
FACILE HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF VARIOUS NANOSTRUCTURED
TITANIA
Erni Astuti1, Yateman Arryanto
2, Indriana Kartini
1,2
1 Functional Coating Materials Research Division, Department of Chemistry, Universitas Gadjah Mada
2Department of Chemistry, Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
Different types of nanostructured TiO2 has been synthesized under hydrothermal condition at
180 °C for 18 hours. TiO2 P25 (Degussa) was used as titanium precursor with mixed solvent
of 10 M NaOH aqueous solution and glycerol. Various volume ratio of NaOH to glycerol
induced different nanostructure types. The volume ratios studied of NaOH:glycerol was 1:0,
2:1 ,1:1, and 1:2. The resulting white precipitates were washed with 0.1 M HCl and deionized
water several times until the filtrate pH was 7. Then, the precipitates were calcined at 350 °C
for 4 hours. X-Ray Diffraction (XRD) patterns show that all TiO2 contain anatase as the
dominant crystalline phase. The one resulted at solvent volume ratio 1:2 has the highest
crystalinity. The bandgap energy of the resulted TiO2 was around 2.73- 3.08 eV promising as
efficient photocatalyst with various nanostructures.
Keywords: nanostructured titania, glycerol, hydrothermal
INTRODUCTION
Titanium dioxide, TiO2, has been widely used in different applications because of its
specific properties, such as photocatalytic activity,photovoltaic effect, medium dielectric
permittivity, high chemical stability, and low toxicity. Photocatalytic and
photovoltaicproperties are influenced by surface area, crystallite size, phasecomposition,
nature and concentration of lattice defects, andimpurities (Gratzel, 2001). TiO2 exists in four
mineral forms (Gianluca et al., 2008), viz: anatase, rutile, brookite and titanium dioxide (B) or
TiO2(B). Anatase type TiO2 has a crystalline structure that corresponds to the tetragonal
system (with dipyramidal habit) and is used mainly as a photocatalyst under UV irradiation.
Rutile type TiO2 also has a tetragonal crystal structure (with prismatic habit). This type of
titania is mainly used as white pigment in paint. Brookite type TiO2 has an orthorhombic
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
10
crystalline structure. While, TiO2(B) is a monoclinic mineral and is a relatively newcomer to
the titania family.
Recently one dimensional nanostructured TiO2, such as nanotube and nanowire have
attracted intensive research interest because of their size and dimensionality-dependent,
physicochemical properties and potensial applications for solar cells/batteries, self-cleaning
coatings, electroluminescent hybrid devices, and photocatalysis (Armstrong et al., 2004).
Therefore, synthesis of one-dimensionalnanostructured TiO2is very important to
study.Considerable efforts have recently beenemphasised on exploring various synthetic
methods. In particular, it has been found that reaction between different TiO2precursors and
concentrated NaOH solution under moderate hydrothermal conditions isan effective approach
to prepare nanotubes and nanowiresbased on titania (Kolen et al., 2006 ; Lan et al.,
2005).Strategiesto control the structure and morphology are more concentrated on varying the
reaction temperature and reaction timeduring hydrothermal treatment. The effect of solvent, as
an important experimental parameter, has scarcely been controlled to result in nanostructures.
Therefore, in this study we aimed at evaluating the effect of volume ratio of NaOH and
glycerol (co-solvent) to the morphology and band gap of the resulted TiO2 under
hydrothermal condition.
MATERIAL AND METHOD
TiO2were synthesized bydispersing 0.67 gram of TiO2(P25 Degussa, which consists of
about 30% of rutile, 70% of anatase, has particle size of about 20 nm) ina 20 mL mixed
solvent of 10 M NaOH aqueous solution and glycerol. The method of TiO2 synthesis was
adapted from Wang et al. (2006), but at various volume ratios of mixed solvent. The volume
ratio of NaOH aqueous solution to theglycerol was 1:0, 2:1, 1:1 and 1:2. After stirring for 1
hour, the suspension were transferred into a Teflon-lined stainless-steelautoclave. The
autoclave was maintained at 180°C for 18 hours andthen cooled to room temperature
naturally. The resulted whiteprecipitate was washed with 0.1M HCl solution and deionized
water several times until the pHwas 7, and finally the precipitate was calcined at 350°C for 4
hours.
X-ray diffraction (XRD) analysis was performed usingXRD-6000 Shimadzu X-ray
diffractometer withmonochromatized Cu-Kα (1.54060 Å). The 2θ range used in the
measurements was from 5o to 70°. The bandgap energy was calculated from Specular-
Reflectancespectra of the TiO2 pellet scanned by UV-Visspectrophotometer (Pharmaspec).
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
11
RESULTS AND DISCUSSION
In this study, nanostructured TiO2was synthesized usinghydrothermalmethodby
controlling the reactionbetween the TiO2precursor powder and various ratio of mixed solvent
of 10 M NaOH aqueous solution and glycerol followed by acid washing and calcination
at350°C. Percent yields of the resulted powders are tabulated in Table 1. It is shown that
when the amount of glycerol increased, the yield decreased. This indicates that the solvent
ratios affect the rate of reactions involved in TiO2 production, particularly hydrolysis and
condensation. It can be seen that the formation of crystalline phases TiO2 was obstructed by
the presence of NaOH. Thus, amorphous phase is the prominent product. The presence of
large amount amorphous solids in the synthesis of metal oxide may contribute to the high
reaction yield.
Table 1. Properties of TiO2powders synthesized at various volume ratio of solvents
NaOH :
glycerol (v/v)
Powder
Yield
(%)
Crystalline
phase
Crystallite
size (nm),
D101
TChkl at highest
value
(> 1)
Eg (eV)
1 : 0 86.00 Amorphous N/A N/A 3.03
2 : 1 82.00 Anatase,
Amorphous
6.57 TC112 (2.45) 2.97
1 : 1 36.00 Anatase 24.88 TC004 (1.31) 2.73
1 : 2 28.35 Anatase 29.55 TC220 (1.99) and
TC004 (1.96)
3.08
Figure 1 shows the XRD patterns of the synthesized TiO2 powders. It can be seen that the
diffraction pattern shows amorphous feature at higher NaOH contents (Fig. 1 (a) and (b))
indicating that solvent system with less glycerol cannot fully achieve the anatase
crystallization. At only in NaOH as the reaction solvent, the formation of an amorphous phase
of titania is indicated by the presence of low intensity broad feature in the range of 2 of 10-
20o and 20
o to 30
o of the corresponding XRD pattern (Fig. 1(a)). The latter peak of this broad
feature shows the averaged distance of Ti atom to other Ti atom (radial distribution function)
of the amorphous titania, which is around 2.3 – 4.5 Å (Williams and Carter, 2006). Figure 1
also demonstrates that all diffraction patterns are dominated with anatase phase. Anatase
crystalinity increases when the amount of glycerol increases. The increasing crystallite size
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
12
(D101) of the synthesized TiO2 at higher content of glycerol (Table 1) also provides strong
indication for increasing crystalinity of anatase TiO2. Yan et al.(2010) reported a facile
ethanol induced hydrothermal synthesis of rutile TiO2 nanotubes without the need of molds or
templates for replication. The synthesis was carried out in ethanol/water solution using the
TiO2 particles with mixed anatase and rutile phase as precursor. The phase transformation
from anatase to rutile was promoted through the chelating role of ethanol to the TiO6
octahedra. They found that the water-ethanol ratio and the type of alcohol have important
influence on the shape and phase structure of the products. In our case, glycerol is predicted to
act similarly as ethanol. However, glycerol did not induce the rutile formation at the assigned
calcination temperature. It may be due to the presence of NaOH as the co-solvent.
Morphological structure of synthesized TiO2 can be predicted from their XRD patterns
by using textural coefficient (TC). Park et al. (2009) has employed the calculation for oriented
ZnO nanorod synthesis. The highest TC value can be an indicator of the product
morphology.Randomly oriented nanoparticles are characterized by TChkl around 1 (Park et al.,
2008). From Fig. 1(a) and (b), the TC cannot be determined since it contains amorphous
phase. TiO2 synthesized at higher glycerol content (Fig. 1(d)) is predicted to have a mixed
morphology of unordered orientation and oriented morphology because it has bimodalhigh TC
value at dhkl (220) and (004). Whereas, Fig. 1(c) has the highest TC value at dhkl
(004)indicating crystalline growth along c-axis, so presented oriented structure that will be
advantageous for device application such as solar cells. Wang et al. (2006) has obtained
nanotubes TiO2 synthesized at NaOH to glycerol volume ratio of 1:1. Polarity and
coordinating ability of a co-solvent may affect strongly on the reactivity behavior of the
reactant, thus influencing the morphology of the resulting products. The nanostructured of
TiO2 synthesized at volume ratio of NaOH to glycerol of 2:1 may display spherical
nanostructures due to its highest TC at dhkl of (112).
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
13
Figure 1 XRD patterns of the synthesized TiO2 at NaOH to glycerol ratios of: (a) 1:0, (b) 2:1,
(c) 1:1, (d) 1:2
(a) TiO2 NaOH:glycerol 1:0 (b) TiO2 NaOH:glycerol 2:1
(c) TiO2 NaOH:glycerol 1:1 (d) TiO2 NaOH:glycerol 1:2
Figure 2 Band gap energy (Eg) of the synthesized TiO2 powders at various solvent volume
ratios
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
14
Figure 2 shows the graphs function for calculating band gap energy from specular reflectance
data. It can be seen that the band gap varies with the solvent ratios. All synthesized TiO2
shows response at visible range of electromagnetic radiation, in the range of 402 to 454 nm.
TiO2 resulted from solvent ratio 1:1 which has predicted nanotube morphology has the highest
visible response. This results pave a way to prepare visible-responsif TiO2 photocatalyst by
using facile hydrothermal methode at various mixed solvent.
CONCLUSION
The synthesized TiO2powders prepared at various mixed solvent of NaOH and
glycerol contain anatase as the dominant crystalline phase. The one resulted at solvent volume
ratio 1:2 has the highest crystalinity and band gap similar as bulk rutile phase TiO2 with
predicted mixed nanostructure morphologies of nanotube and spherical nanoparticles. While,
the one synthesized at solvent volume ratio 1:1 displayed XRD pattern of predicted oriented
nanostructure of nanotube TiO2 with the narrowest band gap. The bandgap energy of the
resulted TiO2 was around 2.73- 3.08 eV promising as efficient visible-responsive
photocatalyst with various nanostructures.
ACKNOWLEDGMENTS
This work was financially supported by research grants from IFS Sweden (F/4089-2)
and Universitas Gadjah Mada under LPPM-UGM/1290/LIT/2013 of Undergraduate Research
Incentives (IPM) 2013.
REFERENCES
Armstrong, A.R.; Armstrong, G.; Canales, J.; Bruce, P.G., 2004, TiO2-B Nanowires,
Angew.Chem., Int. Ed. 43, 2286.
Gianluca, L.P., Bono, A., Krishnaiah, D., Collin, J.G., 2000, Preparation of titanium dioxide
photocatalyst loaded onto activated carbon support using chemical vapor
decomposition: a review paper, J. Hazard. Mater. 157 (2–3). 209–219.
Gratzel, 2001, Photoelectrochemical cells, Nature, 414, 338.
Kolen ´ ko, Y.V.; Kovnir, K.A.; Gavrilov, A.I.; Garshev, A.V.; Frantti, J.; Lebedev, O.I.;
Churagulov, B.R.; Van Tendeloo, G.; Yoshimura, M.J., 2006, Hydrothermal synthesis
and characterization of nanorods of various titanates and titanium dioxide, Phys.
Chem. B. 110, 4030.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
15
Lan, Y.; Gao, X.P.; Zhu, H.Y.; Zheng, Z.F.; Yan, T.Y.; Wu, F.; Ringer, S.P.; Song, D.Y.,
2005. Titanate nanotubes and nanorods prepared from rutile powder. Adv. Funct.
Mater. 15, 1310.
Park,J.H., Lee, T.W., Kang, M.G., 2008,Growth, detachment and transfer of highly-ordered
TiO2 nanotube arrays: use in dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2867-2869.
Park, J.H., Muralidharan, P., and Kim, D.K., 2009, Solvothermally Grown ZnO Nanorod
Arrays on (101) and (002) Single-and Poly-Crystaline Zn Metal Substrates, Mater.
Lett., 63,1019-1022
Wang, Q., Wen, Z., Li, J., 2006, Solvent-controlled synthesis and electrochemical Lithium
storage of one-dimensional TiO2 nanostructures, Inorg. Chem., 45(17), 6944.
Williams, D.B., Carter, C.B., 1996, Transmission Electron Microscopy: A Textbook for
Materials Science. New York: Plenum Press.
Yan, J., Feng, S, Lu, H., Wang, J., Zheng, J., Zhao, J., Li, L., Zhu, Z., 2010, Alcohol induced
liquid-phase synthesis of rutile titania nanotubes,Mater. Sci. Eng. B, 172(2),114.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
17
KOMANGLAWIT (KOMPOR BERBAHAN BAKAR CANGKANG KELAPA SAWIT)
SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENGGANTI KOMPOR MINYAK
Lestari Wevriandini
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
Produksi minyak nabati berbahan dasar kelapa sawit menghasilkan limbah berupa cangkang
kelapa sawit. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti
minyak tanah. Naiknya harga BBM sejak tahun 2005 turut mengakibatkan naiknya harga
minyak tanah. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas,
sebagian masyarakat pedesaan masih enggan menggunakan gas karena belum terbiasa dan
kekhawatiran dari aspek keamanan. Komanglawit (Kompor berbahan bakar cangkang kelapa
sawit) merupakan inovasi untuk memanfaatkan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar
alternatif. Komanglawit didesain dengan sirkulasi udara yang baik sehingga menghasilkan
nyala api yang berkualitas baik. mempengaruhi nyala api yang dihasilkan. Hasil pengujian
menunjukkan penggunaan Komanglawit lebih efisien dibanding kompor minyak. Untuk
memanskan empat liter air dengan Komanglawit dibutuhkan waktu 13 menit 47 detik,
sementara dengan kompor minyak dibuthkan 24 menit 25 detik.Jenis penelitian yang
digunakan merupakan jenis penelitian hipotesis masalah dalam masyarakat dengan
menggunakan metode eksplorasi yang mana dilakukan alternatif penyelesain masalah terkait
dengan limbah kelapa sawit dengan hubungannya dengan kelangkaan dan kenaikan bahan
bakar minyak. Selanjutnya dilakukan desain dan modifikasi kompor sedemikian rupa agar
daya guna kompor semakin banyak.
Keywords : cangkang kelapa sawit, limbah kelapa sawit, bahan bakar alternatif
PENDAHULUAN
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Oktober 2005 memberikan efek
yang besar bagi masyarakat kalangan bawah. Kenaikan harga minyak mulai dari minyak
tanah, bensin dan solar sangat membebani masyarakat miskin, kenaikan harga BBM juga
mengakibatkan berbagai harga barang kebutuhan pokok lainnya ikut naik (Anonim, 2012).
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
18
Kenaikan Bahan Bakar Minyak ini membuat berbagai kalangan mencari berbagai alternatif
pengganti Bahan Bakar Minyak salah satunya limbah cangkang dari tanaman kelapa sawit.
Kelapa sawit (Elaeis guinensis jacq) adalah komoditas penghasil minyak utama di
Indonesia. Banyaknya lahan kelapa sawit di Indonesia seluas 6,7 juta hektar pada 2007,
menjadi 7,4 juta hektar pada 2008 dan tahun ini mencapai 8,2 hektar. Saat ini, produksi kelapa
sawit mencapai 25 ton per tahun (Kurniati, 2008). Hal tersebut menyebabkan banyaknya
produksi kelapa sawit yang menghasilkan banyak limbah yang salah satunya adalah limbah
cangkang kelapa sawit. Limbah cangkang kelapa sawit kurang dapat dimanfaatkan secara
optimal apabila penggunaannya kurang tepat. Salah satu cara untuk memanfaatkan limbah
cangkang tersebut adalah dengan membuatnya menjadi salah satu bahan bakar alternatif. Agar
hasil yang didapat lebih optimal, maka diperlukan sebuah kompor khusus yang menggunakan
limbah cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakarnya. Dengan dibuatnya KOMANGLAWIT
(kompor khusus berbahan bakar cangkang kelapa sawit) diharapkan dapat meminimalisasi
penggunaan bahan bakar minyak untuk kebutuhan memasak rumah tangga sehari-hari dan
juga memaksimalkan daya guna limbah cangkang kelapa sawit, sehingga dapat mengurangi
pencemaran lingkungan akibat kurangnya pengolahan limbah.
MATERI DAN METODE
Pembuatan KOMANGLAWIT ditujukan sebagai upaya pengelolaan limbah kelapa
sawit, khususnya cangkang kelapa sawit terutama oleh masyarakat di sekitar perkebunan,
perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Pelaksanaan program ini menggunakan metode
eksplorasi, yaitu dengan dilakukan penyelidikan ataupun pencarian mengenai pembuatan dan
desain kompor yang paling tepat berbahan bakar cangkang kelapa sawit. Pelaksanaan
memakan waktu lima bulan dimana metode eksplorasi yang digunakan dibagi menjadi 2
tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan sebagai berikut;
1. Pada tahap persiapan dilakukan koordinasi anggota untuk pembagian tugas dalam
pembelian alat dan bahan serta strategi yang dapat dilakukan agar kegiatan dapat berjalan
dengan baik. Setelah dilakukan koordinasi, dilakukan survei tenaga ahli yang akan
membantu pelaksanaan pembuatan KOMANGLAWIT. Selain koordinasi dan survei
tenaga ahli, dilakukan pengadaan alat dan bahan yang diperlukan, seperti limbah cangkang
kelapa sawit akan didapat melalui salah satu masyarakat yang bekerja di perkebunan
kelapa sawit di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, plat besi ketebalan
3mm; pipa besi dan lain-lain.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
19
2. Pada tahap pelaksanaan dilakukan perakitan hingga pembuatan KOMANGLAWIT. Tahap
pelaksanaan akan dilakukan di Dusun Sembungan, Desa Bangun Jiwo, Bantul, Yogyakarta.
Tahap ini dimulai dengan desain ulang KOMANGLAWIT dengan tenaga ahli yang akan
menjadi dasar pembuatan KOMANGLAWIT, kemudian pembuatan kerangka
KOMANGLAWIT, dilanjutkan pemasangan kerangka, pengujian awal KOMANGLAWIT
(nyala api), pembuatan prototype, pengujian akhir kompor (perbandingan dengan kompor
minyak) dan tahap pengecatan (finalisasi). Berikut adalah diagram alir tahap pelaksanaan
progrram pembuatan KOMANGLAWIT;
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenaikan harga BBM memberikan dampak meningkatnya harga bahan-bahan pokok.
Dengan semakin meningkatnya harga bahan bakar minyak maka masyarakat berupaya
mencari berbagai solusi alternatif untuk menanggulangi masalah kenaikan harga tersebut
dengan bahan bakar alternatif. Salah satu sumber bahan bakar alternatif yang mulai banyak
digunakan adalah biomassa, salah satunya limbah dari perkebunan kelapa sawit. Menurut Ma
etal. (2004), produk samping dari pengolahan kelapa sawit adalah cangkang sawit yang
asalnya dari tempurung kelapa sawit. Cangkang sawit merupakan bagian paling keras pada
komponen yang terdapat pada kelapa sawit. Saat ini pemanfaatan cangkang sawit di berbagai
industri pengolahan minyak CPO belum begitu maksimal. Peningkatan Nilai Tambah dari
Limbah Kelapa Sawit dimana cangkang kelapa sawit merupakan salah satu limbah dari
pengolahan minyak kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 30% dari produksi
minyak. Senyawanya terdiri dari konstituen selulosa, hemiselulosa dan lignin. Kelebihan dari
cangkang sawit dibandingkan batubara adalah cangkang sawit lebih ramah bagi lingkungan
dan orang sekitar. Unsur batubara mengandung sulfur dan nitrogen sehingga pembuangan uap
dari boiler akan mengganggu kesehatan masyarakat. Cangkang sawit merupakan bagian
paling keras pada komponen yang terdapat pada kelapa sawit. Dalam hasil penelitian, besar
kalori cangkang kelapa sawit mencapai 20000 KJ/Kg. Saat ini pemanfaatan cangkang sawit di
berbagai industri pengolahan minyak CPO masih belum dipergunakan sepenuhnya, sehingga
masih meninggalkan residu, yang akhirnya cangkang ini dijual mentah ke pasaran. Apabila
dibandingkan dengan tempurung kelapa biasa, cangkang kelapa sawit memiliki banyak
kemiripan. Perbedaan yang mencolok yaitu pada kadar abu yang biasanya mempengaruhi
kualitas produk yang dihasilkan oleh cangkang kelapa sawit.
KOMANGLAWIT merupakan kompor yang bahan bakarnya menggunakan limbah
kelapa sawit, yaitu cangkang kelapa sawit. Seperti telah dijelaskan sebelumnya cangkang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
20
kelapa sawit memiliki potensi sumber energi yang cukup banyak termasuk gas atau asap yang
dihasilkan yang ramah lingkungan. Arang yang terbuat dari cangkang sawit selain memiliki
nilai kalori yang tinggi, juga mengandung sulfur dan abu rendah Gas CO2 yang dihasilkan
dari pembakaran arang dan bukan termasuk kategori Gas Rumah Kaca (GRK). Pembuatan
kompor yang berbahan bakar cangkang kelapa sawit memiliki banyak keunggulan, selain
memanfaatkan limbah, energi yang dibutuhkan pada proses persiapan hingga pembakaran
cangkang lebih sedikit dibandingkan jika cangkang dibuat menjadi briket terlebih dahulu.
Pelaksanaan program pembuatan KOMANGLAWIT diawali dengan desain kompor
yang sebenarnya dasar pembuatan desain menyerupai kompor tungku dari tanah liat yang
telah banyak digunakan oleh masyarakat, namun pada desain KOMANGLAWIT mengalami
berbagai tambahan agar kompor yang dihasilkan memiliki nilai tambah (unggul) dibanding
kompor lain. Hasil yang dicapai selama kurang lebih lima bulan pelaksanaan adalah telah
dibuat sebuah kompor berbahan bakar alternatif yaitu cangkang kelapa sawit dengan bahan
dasar plat besi ketebalan 3 mm. Plat besi yang digunakan bertujuan menambah ketahanan
kompor terhadap panas yang akan dihasilkan oleh bahan bakar. Selain itu, dibuat beberapa
lubang pada bagian pipa besi dan dinding kompor yang bertujuan mengatur sirkulasi udara
(Gambar.1) yang akan berpengaruh terhadap nyala api.
Gambar.1. Sirkulasi udara di dalam KOMANGLAWIT
Desain KOMANGLAWIT awal berbeda dengan desain acuan pada saat pembuatan
karena selain metode yang digunakan adalah metode eksplorasi, pergantian desain
(modifikasi) dilakukan bertujuan untuk menambah kegunaan dari KOMANGLAWIT. Adapun
beberapa modifikasi yang dilakukan, antara lain penambahan lubang sirkulasi udara
(Gambar.1), dudukan panci fleksibel yang bisa diatur sesuai dengan ukuran panci, pegangan
kompor sehingga kompor bisa dibawa/dipindahkan dengan mudah, terdapat tempat khusus
abu yang dapat menampung abu hasil pembakaran, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pupuk
dan lain-lain. Modifikasi yang dilakukan seperti yang telah disebutkan secara teknis memakan
waktu yang paling lama dibanding dengan tahapan yang lain. Hal ini dilakukan karena tujuan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
21
utama dari program adalah membuat sebuah kompor, sehingga dalam hal pengujian dan
lainnya hanya dijadikan sebagai nilai tambah pelaksanaan program yang bisa dikembangkan
kedepannya. Berikut adalah desain awal dan setelah modifikasi KOMANGLAWIT;
Gambar 2. Desain awal KOMANGLAWIT sebelum modifikasi
Gambar 3. Desain KOMANGLAWIT setelah modifikasi
Setelah desain dilakukan maka dilakukan uji coba KOMANGLAWIT untuk melihat
nyala api yang dihasilkan dan efisiensi kompor bila dibandingkan dengan kompor berbahan
bakar minyak. Nyala api yang dihasilkan pada KOMANGLAWIT belum menghasilkan api
biru yang dimungkinkan cangkang sawit masih dalam kondisi lembab dan masih terdapat
campuran sersah tanaman lain yang menempel pada cangkang. Selain uji coba nyala api
dilakukan juga uji coba untuk membandingkan efisiensi KOMANGLAWIT dalam memasak.
Hasil yang didapatkan dari uji coba, yaitu KOMANGLAWIT dapat memanaskan air hingga
mendidih (100° C) selama 13 menit 47 detik dengan keadaan bahan bakar cangkang
memenuhi kompor (tempat bahan bakar). Sedangkan, pada kompor berbahan bakar minyak
dengan nyala api sedang dapat memanaskan air hingga mendidih (100° C) selama 24 menit
25 detik. Hal ini dapat membuktikan bahwa efisiensi KOMANGLAWIT dalam memasak
cukup baik. Hasil yang cukup baik dilanjutkan dengan pembuatan prototype (Gambar
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
22
4.)KOMANGLAWIT yang bertujuan agar dapat lebih mudah dilihat desainnya serta
mengenalkan KOMANGLAWIT pada masyarakat.
Gambar 4. Desain 3D KOMANGLAWIT dan prototype KOMANGLAWIT
Kompor berbahan bakar alternatif terutama limbah sawit telah mulai banyak
dikembangkan, contohnya kompor Gasifikasi PP-Plus yang dusung oleh Joel, dkk (2012)
yang berbahan bakar limbah sawit baik tandan kosong kelapa sawit maupun cangkang kelapa
sawit. Penelitian yang dilakukan memiliki keakuratan yang cukup tinggi dimana dilakukan
secara mendetail ukuran cangkang, berat cangkang hingga densitas cangkang sehingga dapat
diukur nyala api yang benar-benar akurat. Menurut Joel, dkk (2012), cangkang sawit yang
akan digunakan divariasikan dengan ukuran <0.5 cm dan 0.5-1 cm. Cangkang dengan ukuran
<0.5 cm menghasilkan densitas unggun sekitar 0.4 gram/cm3. Kedepannya akan terus
dilakukan pengembangan terhadap KOMANGLAWIT dan peningkatan keakuratan penelitian,
sehingga akan menambah keunggulan dari KOMANGLAWIT dan meningkatkan minat
masyarakat untuk menggunakan KOMANGLAWIT. Hal utama yang ingin dilakukan kedepan
adalah uji coba nyala api hingga dihasilkan api yang bewarna biru, sehingga pembakaran
cangkang di dalam kompor terjadi dengan sempurna yang akan semakin meminimalisir gas
berbahaya yang dihasilkan selama proses pembakaran. Nyala api biru akan sangat mungkin
dicapai berdasarkan penelitian Nurhuda (2011) salah satu dosen jurusan FMIPA Universitas
Brawijaya menerangkan bahwa kelebihan kompor yang berbahan bakar cangkang kelapa
sawit adalah menerapkan empat teknologi, yakni pre-heating, counter flow, diffuse
combustion dan regulation. Dengan harga terjangkau, kompor berbahan bakar cangkang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
23
kelapa sawit memiliki kelebihan diantaranya tidak berasap, efisiensi hingga 40-50% serta
nyala api yang lebih biru dan bersih. Cangkang kelapa sawit memberikan nyala api lebih biru
dan bersih dibanding bahan bakar lain seperti kayu dan seresah daun.
KESIMPULAN
Cangkang kelapa sawit merupakan limbah yang cukup berpotensi untuk dijadikan
sumber energi alternatif bahan bakar minyak. KOMANGLAWIT merupakan salah satu alat
berupa kompor yang dapat memaksimalkan penggunaan limbah cangkang kelapa sawit.
KOMANGLAWIT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya efisien dalam penggunaan
bahan bakar minyak dan waktu, mudah dibawa dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Anoim. 2012. Proyeksi Dampak Kenaikan BBM April 2012.
<http://politik.kompasiana.com/2012/03/12/proyeksi-dampak-kenaikan-bbm-april-
2012/>.Diakses tanggal 15 Oktober 2012.
Azharuddin. 2009. Kompor Bahan Bakar Batok Kelapa. Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya,
Palembang
Bunie, I. S. 2012. Cangkang Diburu Banyak Negara.
<http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148:ca
ngkang-diburu-banyak-negara&catid=52:tren-komoditas>. Diakses tanggal 13
Oktober 2012.
Fauzi,A. P., M. Salleh, M. Shahwahid, A. Rahim, N. A. Noor dan A.G.M. Farid. 2002. Cost
of Harvesting Operations in Compliance with ITTO Guidelines, In N. Abdul Rahim
(ed.) : A model projectfor cost analysis to achieve sustainable forest management 2 :
63-84.
Husin, Andriarti Amir. 2006. Pemanfaatan Limbah untuk Bahan Bangunan. Departemen
Pekerjaan Umum, Bandung.
Joel, S.M., Zulfansyah dan M. I. Fermi. 2012. Kinerja Kompor Gasifikasi PP-Plus Berbahan
Bakar Limbah Sawit. Seminar Nasional Teknik Kimia Indonesia dan Musyawarah
Nasional APTEKINDO. Universitas Indonesia, Jakarta.
Kuncoro, H. dan L. Damanik. 2005. Kompor Briket Batubara. Penebar Swadaya, Jakarta.
Kurniati, E. 2008. Pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai arang aktif. Jurnal Penelitian
Ilmu Teknik VIII 2 : 96-103.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
24
Reksohadiprodjo. 1998. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi edisi kedua. BPFE,
Yogyakarta.
Sopian, T. 2011. Potensi Alternatif Energi Pengganti BBM.
<http://www.alpensteel.com/article/56-110-energi-sampah--pltsa/2582--potensi-
alternatif-energi-pengganti-bbm>. Diakses tanggal 28 Juli 2013.
Suryo, W.P dan R. Armando. 2009. Membuat Kompor tanpa BBM. Penebar Swadaya,
Jakarta.
Walker, L. P. 2008. Invited participant in the joint workshop of the U.S. Dept. of
Energy/Office of Science and the U.S. Dept. of Agriculture, “Sustainability of Biofuels.
State of the Science and Future Directions, Bethesda, MD.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
25
„ANIMAL WASTE INTEGRATED PROCESSING SYSTEM‟ (ANIWASIN PROSYS):
ENERGI RAMAH LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN PETERNAK DUSUN KALIPUCANG, KASIHAN-BANTUL,
YOGYAKARTA
M. Faisol Amir1, Ershalat Tahta Nabhanudin
2, Dwi Abdul Mufi
2
1 Jurusan Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL UGM
2 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
Industri peternakan menyumbang 18 persen gas efek rumah kaca (PBB, 2008). Komponen gas
buangan yang dihasilkan berupa karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitro oksida
(N2O). Prosentase tersebut lebih besar dibandingkan gas rumah kaca yang dihasilkan dari
seluruh moda transportasi di dunia yaitu 13,5 persen. Sementara itu,penggunaan lahan dunia
tidak proporsional. 15 juta km2 lahan pertanian untuk pangan, sedangkan 30 juta km
2 untuk
ternak (FAO, 2011). Gas metana (CH4) dari produk feses ternak memiliki dampak 21 kali
lebih tinggi dibandingkan gas kabondioksida (CO2) dalam menimbulkan pemanasan global
(Wahyuni, 2011). Penanganan limbah yang biasa dilakukan oleh petani dan peternak adalah
dengan menampung di kolam terbuka, sehingga proses fermentasi aerobik dan degradasi
sennyawa organik berlangsung sangat lambat (Kinney, 1962).Animal Waste Integrated
Processing System (Aniwasin Prosys) merupakan program untuk meningkatkan pendapatan
peternak dengan memanfaatkan limbah peternakan dan mengurangi dampak gas metanyang
dapat menimbulkan global warming.Limbah organik peternakan diolah menjadi energi
terbarukan (biogas dan listrik), pupuk organik, dan media ternak cacing.Prosesnya, feses
diolah menjadi biogas, kemudian limbah biogas dimanfaatkan sebagai media ternak cacing.
Pihak yang terkait untuk membantu mengimplementasikan program ini di antaranya peternak,
akademis, dan pemerintah. Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu meningkatkan
produktivitas peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, dan mengurangi penyebab
terjadinya global warming dari limbah peternakan.
Keywords : Aniwasin, Prosys, Alternatif, Peningkatan, Peternak
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
26
PENDAHULUAN
Kalipucang merupakan salah satu dukuh dari 19 dukuh yang terdapat di Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Bantul. Dukuh ini berjarak sekitar 50 kilometer dari Kota Yogyakarta
atau sekitar 45 menit perjalanan jika menggunakan kendaraan bermotor.Dukuh ini dikenal
sebagai salah satu dukuh pengerajin gerabah.Banyak di antara masyarakatnya yang membuat
gerabah, baik sebagai pemilik kerajinan gerabah atau sebagai buruh pengrajin gerabah.
Meskipun demikian, bertani dan beternak masih menjadi mata pencaharian warga. Di
Kalipucang sendiri telah terbentuk kelompok ternak sapi yang diberi nama „Andini Makmur‟.
Dari 40 kandang yang ada, sapi yang diternakkan beragam jenisnya, di antarnaya sapi jenis
PO, angus, simpo, dan limpo. Usia sapi dewasa di kelompok ternak rata-rata ini 2,5 tahun.
Ternak sapi tersebut berfungsi sebagai tabungan bagi pemiliknya.
Setiap harinya seekor sapi bisa menghasilkan limbah feses sebanyak 29 kilogram
untuk sapi potong dan 50 kilogram untuk sapi perah (Wahyuni, 2009). Jenis sapi yang
diternakkan rata-rata adalah sapi potong. Jika dilkalkulasikan, setiap hari peternakan tersebut
mampu menghasilkan limbah feses mencapai 1.160 kilogram. Laporan Perserikatan Bangsa-
Bangsa berjudul Livestock‟s Long Shadow yang disusul Kick the Habit pada tahun 2008
menyebut industri peternakan menyumbang 18 persen gas efek rumah kaca. Komponen gas
buangan yang dihasilkan berupa karbondioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitro oksida
(N2O). Hal ini jauh lebih besar dibandingkan sumbangan gas rumah kaca (karbondioksida)
dari seluruh moda transportasi di dunia yang „hanya‟ 13,5 persen. Feses sapi merupakan
produk utama penghasil gas metan (CH4), karbondioksida (CO2), dsb. Feses sapi memiliki
rasio C/N yang cukup tinggi, yaitu 24. Rasio C/N yang tinggi tersebut menyebabkan limbah
ternak sapi sangat potensial untuk diolah sebagai sumber energi alternatif.
Potensi lembah ternak sapi kelompok ternak Andini Makmur selama ini belum digunakan
secara maksimal. Peternak biasanya hanya menggunakannya langsung sebagai pupuk untuk
lahan pertanian. Belum ada pengelolaan limbah ternak secara terpadu. Melihat potensi limbah
ternak tersebut, diperlukan pengelolaan limbah ternak secara terpadu dari hulu ke hilir untuk
memberikan nilai tambah terhadap limbah ternak. Salah satualternatif potensial untuk
dikembangkan adalah pengelolaan biogas. Selanjutnya, limbah biogas tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk cair dan padat, penghasil tenaga listrik, serta
sebagai media ternak cacing. Pengelolaan limbah peternakan ini menjadi bagian dari usaha
untuk meningkatkan pendapatan petani dan peternak dengan sistem pertanian yang
berwawasan ekologis, ekonomis dan berkesinambungan. Sistem ini sering juga
disebut sustainable mix farming atau mix farming. Sistem mix-Farming, diarahkan pada upaya
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
27
memperpanjang siklus biologis dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil samping pertanian
dan peternakan atau hasil ikutannya, di mana setiap mata rantai siklus menghasilkan produk
baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dengan sistem ini diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat kalipucang.
METODE
Penulisan karya tulis ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi
literatur dan observasi lapangan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. Sementara,
data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai penelitian yang berkaitan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Senyawa organik berlangsung sangat lambat (Kinney, 1962). Hal ini jelas kurang
sedap untuk di pandang dan berbau busuk yang menyengat hidung (terutama pada musim
hujan), dan dapat menjadi sumber polutan utama yang dianggap sebagai permasalahan sosial
(Widarto, 1995). Lebih-lebih bila limbah tersebut di buang ke sungai tentu akan mencemarkan
air sungai yang sangat berbahaya bagi masyarakat pengguna air sungai untuk keperluan
sehari-hari. Walaupun perairan secara alamiah memiliki daya purifikasi tersendiri yang
mampu mengubah bahan-bahan organik tersebut akan terurai atau menjadi hancur, tetapi jika
pencemarannya terlalu tinggi tentu akan sangat membahayakan dan dapat mengganggu
kesehatan masyarakat sekitar (Widarto, 1995). Pada awalnya populasi bakteri pengurai limbah
tersebut jumlahnya cukup besar sejalan dengan meningkatnya polutan, akan tetapi pada suatu
tingkatan tertentu cenderung menurunkan aktivitasnya sejalan dengan semakin terbatasnya
oksigen (O2) yang tersedia dalam perairan tersebut. Hal yang terjadi selanjutnya adalah
timbulnya gas beracun yang berasal dari feses ternak dan dari proses pembusukannya.
Beberapa gas dan senyawa kimia pada feses yang dalam jumlah tertentu akan mengganggu
kesehatan antara lain H2S, metan (CH4), gas-gas lain, amina, merkaptan, sulfida, dan disulfida
(Suryanta, 1995).
Limbah peternakan yang berupa feses memerlukan penanganan secara khusus.
sehingga perlu adanya sistem pengolahan limbah peternakan secara keseluruhan dan
terintegrasi. Program Animal Waste Integrated Processing System (Aniwasin Prosys) adalah
program yang dilakukan dengan mengintegrasikan pemanfaatan feses yang dibuat menjadi
biogas, kemudian limbah biogas dimanfaatkan menjadi media ternak cacing.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
28
Penanganan Lembah Peternakan
Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak
tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain
(unidentified subtances). Limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak,
pupuk organik, energi dan media pelbagai tujuan (Sihombing, 2002).
a. Pemanfaatan Untuk Gasbio
Permasalahan limbah ternak, khususnya manure dapat diatasi dengan
memanfaatkan menjadi bahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Salah satu bentuk
pengolahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan limbah tersebut sebagai bahan
masukan untuk menghasilkan bahan bakar gasbio. Kotoran ternak ruminansia sangat baik
untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Ternak ruminansia mempunyai
sistem pencernaan khusus yang menggunakan mikroorganisme dalam sistem
pencernaannya yang berfungsi untuk mencerna selulosa dan lignin dari rumput atau
hijauan berserat tinggi. Oleh karena itu pada tinja ternak ruminansia, khususnya sapi
mempunyai kandungan selulosa yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh
bahwa tinja sapi mengandung 22.59 persen sellulosa, 18.32 persen hemi-sellulosa, 10.20
persen lignin, 34.72 persen total karbon organik, 1.26 persen total nitrogen, 27.56:1 ratio
C:N, 0.73 persen P, dan 0.68 persen K .
Gasbio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang merupakan
hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob. Gas yang dominan adalah gas
metan (CH4) dan gas karbondioksida (CO2) (Simamora, 1989). Gasbio memiliki nilai
kalor yang cukup tinggi, yaitu kisaran 4800-6700 kkal/m3, untuk gas metan murni (100
persen) mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m3. Produksi gasbio sebanyak 1275-4318 I dapat
digunakan untuk memasak, penerangan, menyeterika dan mejalankan lemari es untuk
keluarga yang berjumlah lima orang per hari.
Pembentukan gasbio dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob yang meliputi
tiga tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. Pada tahap
hidrolisis terjadi pelarutan bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan
organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk primer menjadi
bentuk monomer. Pada tahap pengasaman, komponen monomer (gula sederhana) yang
terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk
asam. Produk akhir dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam asetat,
propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan
amoniak.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
29
Model pemroses gasbio yang banyak digunakan adalah model yang dikenal
sebagai fixed-dome. Model ini banyak digunakan karena usia pakainya yang lama dan
daya tampungnya yang cukup besar, meskipun biaya pembuatannya juga cukup besar.
Untuk mengatasi mahalnya pembangunan pemroses biogas dengan model fixed-
dome, sebuah perusahaan di Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Pengkajian dan
Penerapan Teknolgi Ungaran mengembangkan model yang lebih kecil untuk 4-5 ekor
ternak, yang siap pakai dan lebih murah karena berbahan plastik yang dipendam di dalam
tanah.
Di pedesaan, gasbio dapat digunakan untuk keperluan penerangan dan memasak
sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada minyak tanah ataupun listrik dan kayu
bakar. Bahkan jika dimodifikasi dengan peralatan yang memadai, biogas juga dapat untuk
menggerakkan mesin.
b. Pemanfaatan Untuk Pakan dan Media Ternak Cacing Tanah
Sebagai pakan ternak, limbah ternak kaya akan nutrien seperti protein, lemak
BETN, vitamin, mineral, mikroba dan zat lainnya. Ternak membutuhkan sekitar 46 zat
makanan esensial agar dapat hidup sehat. Limbah feses mengandung 77 zat atau senyawa,
namun di dalamnya terdapat senyawa toksik untuk ternak. Untuk itu, pemanfaatan limbah
ternak sebagai makanan ternak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Tinja ruminansia
juga telah banyak diteliti sebagai bahan pakan termasuk penelitian limbah ternak yang
difermentasi secara anaerob.
Penggunaan feses sapi untuk media hidupnya cacing tanah telah diteliti
menghasilkan biomassa tertinggi dibandingkan campuran feces yang ditambah bahan
organik lain, seperti feses 50 persen + jerami padi 50 persen, feses 50 persen + limbah
organik pasar 50 persen, maupun feses 50 persen + isi rumen 50 persen (Farida, 2000).
c. Pemanfaatan Sebagai Pupuk Organik
Kotoran ternak juga banyak dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penggunaan
pupuk kandang (manure) selain dapat meningkatkan unsur hara pada tanah juga dapat
meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan memperbaiki struktur tanah
tersebut.Kandungan Nitrogen, Posphat, dan Kalium sebagai unsur makro yang diperlukan
tanaman tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 1. Kadar N, P dan K dalam Pupuk Kandang dari Beberapa Jenis Ternak
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
30
Jenis Pupuk
Kandang
Kandungan ( persen)
N P2O5 K2O
Kotoran Sapi
Kotoran Kuda
Kotoran Kambing
Kotoran Ayam
Kotoran Itik
0.6
0.4
0.5
1.6
1.0
0.3
0.3
0.3
0.5
1.4
0.1
0.3
0.2
0.2
0.6
Sumber: Nurhasanah, Widodo, Asari, dan Rahmarestia (2006)
Kotoran ternak dapat juga dicampur dengan bahan organik lain untuk
mempercepat proses pengomposan serta untuk meningkatkan kualitas kompos.
d. Pemanfaatan Lainnya
Selain dimanfaatkan untuk pupuk, bahan pakan, atau gasbio, kotoran ternak juga
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan mengubahnya menjadi briket dan
kemudian dijemur atau dikeringkan. Briket ini telah dipraktikkan di India dan dapat
mengurangi kebutuhan akan kayu bakar. Pemanfaatan lain adalah penggunaan urin dari
ternak untuk campuran dalam pembuatan pupuk cair maupun penggunaan lainnya.
Peningkatan Pendapatan Peternak
Melalui pemanfaatan limbah peternakan yang terintegrasi, pternak diharapkan mampu
meningkatkan nilai jual limbah yang selama ini kurang dimanfaatkan. Peningkatan nilai jual
limbah peternakan yang seperti dijelaskan di atas merupakan role model paling ideal yang
bisa diterapkan. Melalui Aniwasin Prosys, nilai tambah limbah mampu memberikan
kontribusi pendapatan yang cukup signifikan bagi peternak, sehingga kesejahteraan peternak
dapat meningkat secara berkala.
KESIMPULAN
Limbah usaha peternakan berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan.
Dari komposisinya, kotoran ternak masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan, media
pertumbuhan cacing, pupuk organik, gas bio, dan briket energi. Pemanfaatan limbah ternak
akan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah, maupun udara.
Pemanfaatan tersebut juga menghasilkan nilai tambah yang bernilai ekonomis . Pengelolan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
31
limbah peternakan dengan menggunakan sistem pertanian yang berwawasan ekologis,
ekonomis dan berkesinambungan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem ini juga
ramah lingkungan. Dengan demikian, permaslahan limbah peternakan dapat diatasi dengan
sisitem pengelolahan yang ramah lingkungan serta dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif dan meningkatkan pendapatan peternak masyarakat kalipucang.
DAFTAR PUSTAKA
Farida E. 2000. Pengaruh Penggunaan Feses Sapi dan Campuran Limbah Organik Lain
Sebagai Pakan atau Media Produksi Kokon dan Biomassa Cacing Tanah Eisenia
foetida savigry. Skripsi Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. IPB, Bogor.
Sofyadi Cahyan, 2003. Konsep Pembangunan Pertanian dan Peternakan Masa Depan. Badan
Litbang Departemen Pertanian. Bogor.
Sihombing D T H. 2000. Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan. Pusat
Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor
Soehadji, 1992. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah
Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
Junus, Mohammad. 1987. Teknik Membuat dan Memanfaatkan Unit Gas Bio. Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
33
“AISOC”ANIMAL INCUBATOR WITH AUTOMATICCOLOSTRUM SYSTEM
Dwi Kristanto1, Fivien Fidiyanti
2, Saprindo Harun Prabantara
3, Agus Wigiardi
4, Birrul
Qodriyyah5, Dr. drh. Irkham Widiyono
1
1Faculty of Veterinary Medicine Gadjah Mada University
2 Faculty of VocationalAnimal Health Sciences Gadjah Mada University
3Faculty of Engineering Gadjah Mada University
4Faculty of Sciences Gadjah Mada University
5Faculty of Medicine Gadjah Mada University
ABSTRACT
Bacground: The most problem that faced by Etawa farm is high rates of mortality in the pre-
weaning period (37,5%) which is the critical phases of growth in goats. These conditions
decreased the productivity of goats and making disadvantages in farm business. It can be
prevents by proper management that supported with adequate nutritional intake. So, it needs
an innovation of tools with special design “automatic colostrum” to avoid death in pre-
weaning period and increasing the goat productivity. Methods: Experimental design is using
in this research. Some literature supported with discussions with some veterinary and
engineering experts tool design, manufacture and test the effectiveness of the tool. Result: The
creation of specialized tools such as incubators for pre-weaning goat with colostrum
automated system. Consists of three main subsystems, there are temperature control, humidity
control, and automatic colostrum, supported with mechanical subsystems to create an
effective and efficient equipment in reducing the number of death in the pre-weaning phase.
Goats which getting a with AISOC have the resilience and better health conditions compared
with goats that do not get a treatment using AISOC. Conclutions: AISOC is an incubator with
nutrients control system especially in colostrum automated with temperature and humidity
control that supported in accordance with the needs of goats. This tool is equipped with
alarms to ensure the security and safety of goats. This tool is highly recommended for the
treatment of animals on large or small farms during pre-weaning phase to improve
productivity and reduce the risk of death in animals.
Keywords: Animal Incubator, automatic colostrum, AISOC, pre-weaning phase,
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
34
PENDAHULUAN
Kambing merupakan ruminansia dengan populasi terbesar di Indonesia yang
jumlahnya mencapai sekitar 17.905 (Direktorat Jendral Peternakan, 2013). Usaha ternak
kambing mempunyai peran yang sangat strategis dan prospek yang baik sebagai pemasok
protein hewani maupun sumber devisa. Namun demikian, usaha peternakan pada
kenyataannya masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah tingginya
kematian kambing yang hampir seluruhnya (93,9%) terjadi pada periode pra sapih (Widiyono
cit Rangkuti, 2003).
Berdasarkan beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa kematian anak pra sapih pada
kambing lokal di Indonesia berkisar10-50% (Haryanto, 1997). Sutama et al. (1995)
melaporkan kematian anak kambing Peranakan Etawah (PE) periode pra-sapih pada
penelitiannya mencapai 37,5 %. Angka ini sebanding dengan laporan Setiadi dan Sitorus
(1984) yang menyatakan bahwa tingkat kematian anak kambing Peranakan Etawah (PE)
periode pra-sapih pada penelitiannya mencapai 34,2%. Hal ini juga sesuai dengan penelitian
Rook et al.(1990) yang menyebutkan bahwa pola kematian kambing meningkat pada usia pra
sapih.
Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kematian kambing usia pra sapih adalah
dengan memanajemen penyebab kematian tersebut. Ehrhardt(2013) research showthat
benchmarks for success vary according to production level and management sys-tem.
Penyebab kematian anak kambing pra-sapih diantaranya adalah induk kesulitan melahirkan
(dystocia), pengaruh iklim, sifat keindukan, faktor genetik, jumlah anak dilahirkan,
tatalaksana pemberian pakan, bobot lahir anak, perawatan dan infeksi penyakit (Widyaningsih
cit Puslitbangnak, 2000). Hasil penelitian Chniter et al. (2012) menunjukkan bahwa kambing
yang lahir kembar 3 dan kembar 4 memiliki ukuran berat badan, suhu rektal, serta kadar
plasma metabolit lebih rendah dibandingkan dengan kelahiran kembar 2 selama 3 hari
pertama sejak kelahiran, sehingga memperkecil peluang domba untuk dapat bertahan hidup.
Alexander on Simms (1971) reported that small lambs resulting from twin births, or single
births from ewes receiving a sub-standard gestation ration exhibited a more pronounced
postnatal temperature decrease than individuals of heavier birth weights. Consequently
the level of heat losses in twins, which had lower birth weight, would be higher because of the
presumably larger body surface (Mullerand McCutcheon, 1991).
Permasalahan yang ada hingga saat ini adalah belum ditemukanan alat kedokteran hewan
yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Perawatan yang dilakukan hingga
saat ini masih menggunakan cara konvensional dengan memanipulasi suhu dan keadaan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
35
lingkungan sebagai upaya untuk mencegah kematian kambing. Although, animal production
is not related to a single trait or characteristic, but includes adaptation to the environment,
disease and parasite resistance, nutritional parameters, production and body indices as well
as reproductive traits, among others (Manus, 2011).
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat dengan desain khusus berupa Animal
Incubator With Automatic Colostrum System yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi dunia
kedokteran hewan maupun peternak kambing dalam menekan angka kematian kambing,
sehingga peternak terhindar dari kerugian dan dapat meningkatkan pendapatan dari usaha
ternaknya.
MATERI DAN METODE
Pengujian alat yang dilakukan meliputi uji mekanik dan uji fungsional elektronis
hardware alat. Uji mekanik dilakukan untuk mengetahui tingkat ketahanan alat dalam
menahan beban, sedangkan uji fungsional alat dilakukan untuk mengetahui efektifitas kinerja
fungsional alat dalam mengatur kelembaban dan suhu pada ruang inkubator AISOC.
Pengujian dilakukan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 29, 30, dan 31 Juli 2013. Alat ukur
yang digunakan dalam pengujian meliputi termometer ruangan, termohigro (humidity
measurement), serta jangka sorong untuk mengukur kelengkungan plat terhadap tahanan
beban.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pembuatan Alat
Melalui perancangan alat, sistem inkubator akan didesain dengan dua sistem kategori
besar. Kategori pertama adalah sistem mekanik dan kategori kedua meliputi sistem hardware
elektronik serta program kendali.
Sistem Mekanik
Kategori sistem mekanik akan dibangun dengan tiga subsistem yang meliputi subsistem
pemilihan bahan, subsistem pengerjaan, dan subsistem kerja.
1. Pemilihan bahan
Setelah mempertimbangkan beberapa variabel meliputi: kemampuan menahan berat beban
dan pergerakan anak kambing, ketahanan terhadap kondisi di dalam inkubator (suhu dan
kelembaban), serta daya tahan terhadap keasaman yang ditimbulkan dari air seni maupun
kotoran kambing, maka bahan yang dipilih adalah besi. Pemilihan besi sebagai alternatif
bahan dikarenakan besi memiliki kekuatan yang mampu menopang beban dinamis dari anak
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
36
kambing serta pengerjaan besi cenderung lebih mudah karena dapat dilakukan dengan
pengelasan. Besi terlebih dahulu dilapisi dengan meni (lapisan dasar sebelum pengecatan) dan
dicat untuk menghindarkan sifat korosif apabila terkena asam serta tidak membahayakan
kesehatan kambing yang berada di dalam inkubator.
2. Pengerjaan
Besi yang digunakan sebagai bahan dasar kerangka berukuran 3cmx3cm dan dikerjakan
dengan sistem pengelasan. Las dipilih sebagai metode dalam pengerjaan karena tingkat
kekuatannya bagus dan aman untuk menahan beban, serta pengerjaannya paling mudah
dibandingkan dengan sistem keling atau refet. Selain itu, las memiliki kelebihan berupa
tingkat presisi yang tinggi sehingga diharapkan hasil akhir kerangka sesuai dengan design
autodesk inventor pada software.
3. Sistem kerja
Mekanik inkubator dioperasionalkan menggunakan prinsip kerja manual dengan bagian
penting meliputi:(1)Ruang utama, yaitu ruang inkubasi tempat kambing diberikan perawatan
dan perlakuan khusus. Ukurannya130 cm (panjang), 75 cm (lebar), dan 100 cm (tinggi).
Ukuran dirancang cukup besar agar anak kambing dapat bergerak aktif serta berada dalam
posisi berdiri. Ruangan dibatasi enam sisi. Bagian depan, samping kanan, dan atas dari bahan
acrilic setebal 5 mm. Sementara bagian belakang, samping kanan, dan bawah dengan bahan
plat besi yang dicat setebal 0,5 mm; (2) Ruang A1 merupakan area kompartemen elektronis
yang terdiri dari tiga bagian utama. Pada area ini, terdapat pintu kecil dengan sistem membuka
ke samping untuk memudahkan akses pengguna pada area elektronis kompartemen;(3) Ruang
A2 merupakan ruang sistem pemisah urin serta kotoran kambing (padat dan cair) yang terdiri
dari: 1) Pintu yang merangkap fungsi sebagai bak penampung urin, dioperasionalkan dengan
ditarik untuk membuang dan membersihkan urin serta kotoran kambing; 2) Slorokan
berfungsi sebagai penampung kotoran padat dioperasionalkan dengan ditarik ke luar. Slorokan
terbuat dari plat besi berlapis meni dan cat untuk menghindari terjadinya karat. Pengguna
dapat rutin membersihkan slorokan dengan disemprot dan diberi antioksidan; (4) Ruang A3
merupakan kompartemen area penyimpanan perkakas perawatan kambing yang digunakan
selama kambing berada dakam inkubator. Terdapat pintu penutup yang berfungsi menutup
ruang A1 dan A2. Pintu berbahan acrilic dengan ketebalan 3x3 mm, dioperasionalkan dengan
dibuka kebawah dan tertutup rapat dengan kancing pengunci sehingga seluruh uap air yang
dihasilkan akan masuk ke dalam ruang bakar secara sempurna.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
37
Sistem Hardware Elektronik
Sistem ini terdiri dari 3 subsistem, meliputi subsistem kendali suhu, subsistem kendali
kelembaban udara, dan subsistem kendali suhu colostrum. Adanya subsistem kendali suhu
dan kendali kelembapan udara bertujuan untuk mengadaptasikan hewan yang diinkubasi pada
kondisi lingkungan (suhu dan kelembapan udara) yang terjaga dan sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi hewan. Pada hewan-hewan pasca kelahiran terutama anak kambing, masa tersebut
sangatlah rawan mengingat kondisi dari hewan berada pada titik lemah. Dengan adanya
kendali pada dua parameter tersebut diharapkan kondisi hewan dapat dijaga dengan baik.
Selain dua subsistem tersebut, terdapat subsistem kendali suhu colostrum yang bertujuan
untuk memertahankan suhu colostrum di area penyimpanan agar tetap sehat untuk dikonsumsi
kambing. Colostrum pada area penyimpanan akan dijaga pada suhu dingin, selanjutnya akan
melalui proses pemanasan pada alat sebelum diberikan pada hewan.
Dari diagram blok tersebut terdapat lima blok besar yang mewakili urutan kontrol
proses di dalamnya. Pertama, blok input dimana elemen-elemen di dalamnya merupakan
variabel yang perlu diukur. Variabel tersebut antara lain (sesuai dengan tiga subsistem yang
dirancang) suhu ruangan inkubator (°C), kelembapan udara ruangan inkubator (%RH), dan
suhu kolostrum (°C). Ketiga nilai dari variabel tersebut diukur menggunakan sensor yang
sesuai dalam hal ini digital sensor SHT15 dan DHT11 untuk mengukur suhu serta kelembapan
udara di dalam ruangan inkubator, sedangkan digital sensor DS18B02 digunakan untuk
mengukur suhu dari colostrum. Sensor DS18B02 sendiri merupakan sensor suhu yang
waterproof dan RoHS compliment sehingga aman digunakan pada cairan konsumsi. Ketiga
sensor ditempatkan sedemikian rupa agar dapat men-sensing variabel yang diukur dengan
baik. Blok kedua adalah blok summing circuit. Blok ini merupakan bagian yang digunakan
untuk pembanding antara nilai set point dengan variabel element terukur. Blok ini juga yang
digunakan untuk menerima nilai dari set poin untuk masing-masing value dari variabel yang
akan dimanipulasi. Nilai dari blok input dan blok summing circuit diumpankan menuju blok
kontroler untuk selanjutnya dilakukan pengendalian.
Blok ketiga merupakan blok kontroler yang digunakan untuk melakukan kendali
penyesuaian nilai variabel termanipulasi menggunakan beberapa algoritma kendali. Algoritma
yang digunakan antara lain kontroler PI dan PID yang diterapkan pada kendali suhu dan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
38
kelembapan udara ruangan inkubator. Kendali sederhana on-off digunakan untuk mengontrol
beberapa perangkat bersumber daya AC seperti mist maker, pompa, dan heat filament.
Hardware kontroler yang digunakan pada sistem ini memanfaatkan mikrokontroller ATMega
2560 dengan detak terpasang pada 16 MHz. Kontroler ini dipilih dengan mempertimbangkan
fitur seperti jumlah I/O pin dan banyaknya jalur komunikasi serta biaya implementasi yang
perlu dikeluarkan. Sensor-sensor yang digunakan ketiganya menggunakan jalur komunikasi
i2c dan telah didukung dengan baik oleh kontroler ini dengan menambahkan rangkaian pull-
up. Perangkat input dan visualisasi yang memanfaatkan komponen keypad, tombol, serta LCD
membutuhkan jumlah pin yang cukup banyak dan teraktualisasi dengan baik. Detak yang
terpasang juga dapat mengakomodir kebutuhan kecepatan dari implementasi sistem.
Aktuator-aktuator yang telah disebutkan tadi ditambah dengan aktuator fan merupakan
bagian dari blok keempat. Blok keempat tersebut merupakan bagian dari elemen-elemen
aktuator yang menerima perintah dari blok kontroller untuk men-generate aksi agar nilai dari
variabel yang termanipulasi dapat meraih nilai dari nilai variabel yang diinginkan. Aktuator
mist maker digunakan untuk menghasilkan uap air dengan cara menembak air dengan
gelombang ultrasonik. Uap air yang dihasilkan digunakan untuk memanipulasi variabel
kelembapan udara. Perangkat ini diletakkan di dalam kompartemen air yang ditempatkan pada
bagian kiri dari ruangan utama inkubator dan dialirkan lewat tunnel khusus. Untuk membantu
kerja dari aktuator mist maker digunakan aktuator fan untuk membuat sirkulasi udara di dalam
ruangan inkubator berputar dan keluar dengan baik. Fan yang digunakan berjumlah dua, satu
fan ditempatkan di bagian dinding samping berfungsi untuk menarik udara dari luar ke dalam.
Sedangkan satu fan lagi ditempatkan di bagian atas dinding inkubator dan berfungsi
mengalirkan udara di dalam inkubator keluar. Dengan mekanisme seperti ini maka aliran
udara di dalam inkubator dapat terus-menerus disirkulasikan. Dua fan ini dikendalikan
menggunakan kontroller PID dengan memanipulasi kecepatan dari kedua fan. Untuk dapat
menggerakkan kedua fan digunakan rangkaian kontroller tambahan berupa driver motor.
Aktuator heat filament diimplementasikan menggunakan filamen lampu pijar. Aktuator ini
ditempatkan di bagian langit-langit dalam dari ruangan inkubator di bagian belakang dari
aktuator fan. Filamen ini digunakan untuk memanipulasi variabel suhu ruang. Aktuator ini
terhubung langsung dengan sumber daya AC sehingga kontrol yang diterapkan adalah kontrol
on-off. Aktuator yang terakhir adalah logam peltier yang digunakan untuk memanipulasi suhu
dari colostrum. Seperti diketahui bahwa colostrum disimpan dalam suhu dingin dan kemudian
dipanaskan ketika akan diberikan ke hewan. Proses mendinginkan dan memanaskan ini
menggunakan logam peltier, sebuah logam yang apabila dialiri listrik maka satu sisinya akan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
39
dingin dan satu sisi lagi akan panas. Aktuator ini bekerja dengan sumber daya AC dan
dikontrol menggunakan kontroler on-off.
Aksi yang dilakukan oleh aktuator akan mempengaruhi proses yang berlangsung
dalam sistem, yang merupakan bagian dari blok kelima. Blok kelima ini memiliki input
berupa nilai dari variabel yang termanipulasi. Dan output dari blok ini adalah nilai dari
variabel yang terkontrol. Nilai dari variabel yang terkontrol ini kemudian masuk kembali pada
summing circuit untuk selanjutnya dibandingkan kembali dengan nilai dari set poin yang telah
dimasukkan pengguna. Proses kendali akan terus dilakukan secara sekuensial sampai nilai
dari set point variabel yang ingin dikontrol tercapai dan ditunjukkan sebagai jalur feedback.
Setelah diagram blok konsep sistem selesai dirancang, desain sistem diterapkan dalam
konsep desain hardware elektronik dan program sesuai dengan spesifikasi sistem inkubator
AISOC. Hardware yang didesain dan diimplementasikan antara lain adalah sistem minimum
dari kontroler, kemudian rangkaian pewaktu real time, rangkaian input keypad dan tombol,
rangkaian media LCD, rangkaian sensor, rangkaian driver motor, serta rangkaian smart relay.
B. Pengujian Alat
Uji Mekanik Alat
Uji mekanik dilakukan untuk mengetahui tingkat kekuatan alat dalam menahan
beban. Selanjutnya, hasil uji mekanik ini digunakan untuk memprediksikan berat beban
kambing yang mampu ditahan oleh inkubator. Uji mekanik dilakukan dengan memberikan
beban pada ruangan dalam inkubator dengan vareasi beban yang ditambahkan terus
meningkat dengan interval 1 kg. Pengujian dilakukan pada beberapa area penting yang
menjadi titik kekuatan mekanik alat, meliputi bagian tengah, bagian pojok kanan atas serta
bagian pojok kiri bawah. Alat dianggap sudah tidak mampu menahan beban (beban tahanan
maksimal), saat ditemukan lengkungan pada alat. Digunakan jangka sorong dengan ketelitian
0,02 mm untuk mengukur kelengkungan pada alat. Jangka sorong dipilih karena memiliki
tingkat ketelitian yang tinggi dalam mengukur kelengkungan logam.
Dari uji mekanik tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kelengkungan logam pada alat
ketika diberikan beban sebanyak 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg hingga 8 kg. Hasil pengukuran
tersebut dapat diestimasikan jumlah beban anakan kambing yang dapat dimasukkan ke dalam
inkubator.
Berdasarkan penelitian Widiyono et.al., (2003) yang dilakukan pada 45 ekor kambing
jenis Ettawa usia 1-90 hari, rata-rata berat badan anakan kambing adalah 3, 52 kg dan
memiliki tren meningkat sekitar 1 kg setiap minggunya. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
40
Simms pada 48 Pleven black head (PBH) lambs, 41 Bulgarian fine wool breed x East-Friesian
(FC) crosses-F2 and 48 Bulgarian fine wool breed (BFW) lambs dengan hasil rata-rata berat
badan normal twins lamb adalah 3,8 kg. Menurut penelitian tersebut, the twins had in all
occasions significantly lower birth weight compared with single lambs. Penelitian Chniter et
al., (2012) menunjukkan bahwa kambing yang lahir kembar 3 dan kembar 4 memiliki ukuran
berat badan lebih rendah dari pada single lamb atau twin lambs.
Dengan demikian berat kambing yang dapat ditahan oleh alat adalah sekitar 8 kg. Jika
kambing dengan berat badan normal yang dimasukkan, maka sekitar 3-4 ekor kambing dapat
ditahan oleh inkubator. Jumlah tersebut akan meningkat apabila anakan kambing yang
dimasukkan ke dalam inkubator tergolong dalam prematur atau underweight.
Uji Elektronis Hardware Alat
Uji fungsional alat dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu: 1) Lama waktu yang
diperlukan untuk menghasilkan suhu dan kelembaban sesuai input suhu serta kelembaban
yang diinginkan; 2) Uji automatisasi alarm pada alat apabila terjadi overheating pada ruangan
inkubator; 3) Sinkronisasi vareasi suhu dan kelembaban yang dihasilkan dari data yang
diinputkan.
1. Respon alarm terhadap vareasi suhu yang diinputkan
Pengguna alat dapat menyetting suhu maksimal pada alat sesuai dengan rentang suhu
yang dibutuhkan oleh goat lamb dalam inkubator. Selanjutnya keadaan suhu dalam inkubator
akan ditunjukkan dalam layar LCD. Sistem alarm disetting secara otomatis sebagai petunjuk
tanda bahaya apabila terdapat gangguan pada alat yang menyebabkan suhu di dalam
inkubator melebihi standar suhu maksimal yang telah disetting oleh pengguna. Respon alarm
ini ditunjukkan dengan menyalanya layar LCD dan LED. Dengan adanya alarm ini, user dapat
dengan mudah mengetahui apabila ada bahaya tanpa harus terus menerus mengontrol
inkubator.
Suhu paling maksimal yang diujikan pada alat adalah 39oC. Hal ini mengacu pada
beberapa penelitian sebelumnya seperti Widiyono et al.,(2003) yang menemukan bahwa
temperatur tubuh selama 3 bulan pertama kehidupan kambing berada pada level yang sama,
yaitu sekitar 39oC. Penelitian Aleksinev, et al, (2007) pada tiga jenis peranakan kambing
selama 24 jam pasca kelahiran meyimpulkan bahwa fluktusi suhu rektal pada 24 jam pertama
setelah lahir pada semua kelompok domba sejenis tanpa dipengaruhi vareasi suhu lingkungan,
jenis kelamin dan tipe kelahiran, yaitu berkisar antara 39-40oC dan cenderung mengalami
penurunan seiring bertambahnya jam pasca kelahiran. Whittier menambahkan bahwa
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
41
temperatur suhu dalam ruang penghangat untuk goat lamb with hypotermi tidak boleh
melebihi suhu 103oF. Panas terlalu tinggi diatas suhu tersebut dapat membahayakan anak
kambing.
Hasil ujimenunjukkan hasil respon alarm terhadap vareasi pengaturan suhu maksimal
yang diberikan. Suhu ditingkatkan secara bertahap dengan interval 2oC dengan mendekatkan
filamen panas pada sensor suhu. Hasil uji menunjukkan bahwa alarm dapat berfungsi dengan
baik pada seluruh rentang suhu dengan interval 2oC, ditandai dengan menyalanya LCD dan
LED sebagai petunjuk overheating telah terjadi pada ruang inkubator.
2. Respon alarm terhadap vareasi kelembaban udara yang diinputkan
Selain faktor suhu lingkungan dalam inkubator, kelembaban menjadi faktor penting yang
menunjang stabilitas suhu dalam tubuh kambing. Goats rely on evaporative cooling from the
respiratory tract. Consequently, high humidity associated with high temperatures is stressful to
the animals as it interferes with their ability to regulate body temperature. If indoor
temperatures rise above 30°C (85°F), a comfortable environment can be maintained by
keeping the relative air humidity below 60%.
Respon alarm terhadap setting kelembaban udara diuji dalam rentang 50-75% RH
dengan interval kelembaban 5% RH. Pengujian kelembaban dilakukan dengan cara
menghembuskan nafas dengan berbagai intensitas aensor kelembaban. Hasil uji menunjukkan
bahwa alarm dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tingkat kelembaban maksimal yang
diinputkan oleh user. Seperti halnya pada respon alarm suhu, LCD dan LED menyala pada
saat tingkat kelembaban berada di atas kelembaban maksimal yang telah ditetapkan oleh user.
Dalam pengujian tersebut, alarm aktif pada setiap interval rentang kelembaban % RH yang
diujikan oleh peneliti.
3. Respon kendali alat terhadap vareasi suhu dan kelembaban
Pengujian dilakukan untuk mengetahui respon set suhu dan kelembaban terhadap suhu
serta kelembaban aktual yang ditimbulkan dalam ruang inkubator serta lama waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai suhu yang diinputkan oleh user. Pengujian suhu dilakukan
dengan interval suhu 1oC agar dapat diketahui secara jelas selisih suhu aktual beserta waktu
yang diperlukan pada setiap perbedaan nilai suhu yang diinputkan. Uji terhadap kelembaban
dilakukan dengan interval 0,5% RH dengan rentang kelembaban 60-65% RH.
Dari hasil pengujian suhu yaitu terdapat selisih antara suhu yang diinputkan dengan suhu
aktual pada ruang inkubator. Rata-rata perbedaan tersebut adalah 1, 92oC dari suhu yang
diinputkan. Sedangkan rata-rata lama waktu yang dibutuhkan hingga ruangan inkubator
memiliki suhu sesuai dengan suhu yang diinputkan adalah 325 seconds (5 minutes and 25
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
42
seconds). Input suhu 27 o
C paling sesuai dan mendapatkan respon paling cepat dibandingkan
dengan suhu yang lainnya. Adanya selisih suhu tersebut diperkirakan akibat ada beberapa area
ruang inkubator yang belum tertutup dengan rapat, sehingga dimungkinkan masih ada udara
ataupun pengaruh dari lingkungan luar yang masuk ke dalam ruang inkubator. Hal tersebut
akan memengaruhi kinerja inkubator.
Hasil uji kelembaban dengan konstantan KP (11) dan KD (40) menunjukkan rata-rata
selisih antara kelembaban yang diinputkan dengan kelembaban aktual adalah 2,11% RH
dengan rataan lama waktu untuk mencapaia kelembaban yang diinginkan adalah 259,8 sekon.
Sedangkan uji kelembaban dengan konstantan KP (9) dan KD (27) menunjukkan rata-rata
waktu lebih lama untuk mencapaia kelembaban yang diinginkan, yaitu 436, 33 sekon.
Berdasarkan The results of Aleksinev research (2007) suggest that under prevailing
management system and specific conditions in the barn the newborn lambs of the studied
breeds were able to maintain successfully their body temperature at a range of ambient
temperature 0.0 – 8.0 °C without any incidence of hypothermia. So, inkubator ini sangat
menolong untuk anakan kambing dengan kondisi kritis dan membutuhkan penanganan
khusus.
KESIMPULAN
AISOC is an incubator with nutrients saving system especially in colostrum with
temperature and humidity control that supported in accordance with the needs of goats. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa alat AISOC memiliki ketahanan mekanik 10 kg, serta
dapat mengatur suhu dalam ruang inkubator sesuai dengan suhu yang diinputkan oleh user
dengan waktu capaian suhu dan kelembaban kurang dari 5 menit . Terdapat sedikit perbedaan
antara input dengan hasil aktual yang kemingkinan disebabkan karena ada area ruang
inkubator yang belum tertutup rapat. Setting alarm tanda over heat pada alat dapat berfungsi
dengan baik. This tool is highly recommended for the treatment of animals on large or small
farms during pre-weaning phase to improve productivity and reduce the risk of death in
animals.
DAFTAR PUSTAKA
Aleksiev, Y., D. Gudev And G. Dimov. 2007. Thermal status in three breeds of newborn
lambs during the first 24 hours of postnatal life. Bulgarian Journal of Agricultural
Science., 13: 563-573.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
43
Alexander G.1962.Temperature regulation in the new-born lambIV. The effect of wind and
evaporation of water from the coat on metabolic rate and body temperature.
Australian Journal of Agricultural Research 13(1) 82 - 99
Alexander G. 1974. Heat Loss from Animals and Man Monteith JL and Mount LE (eds).
London: Butterworth.
Boujenane. 2012. Productivity of Sardi, D‟man and their crossbred ewes mated to
terminal sires respectively. Small Ruminant Research Journal. Morocco :
Department of Animal Production and Biotechnology, Institut Agronomique.
Chniter, Mohamed, et. al,. 2012. Aspects of neonatal physiology have an influence on lambs‟
early growth and survival in prolific D‟man sheep. Small Ruminant Research The
Official Journal of the International Goat Association. Accessed on July, 30 pukul
14:24WIB.
Choliq, C. 1992. Studi gambaran kimia darah dan hemogram sederhana dari anak sapi
penderita diare. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Donkin, E.F. and P.A. Boyazoglu. 2004. Diseases and mortality of goat kids in South
Africa milk goat herd. South Africa. J. Anim. Sci. 34 (suppl.) 258- 261.
Ehrhardt, Richard. 2013. Small Ruminant Extension Specialist. US: American Sheep
Industry Association.
Evelyn Pearce, 1991, Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.
Ginting,S.P. 2009. Pedoman Teknis Pemeliharaan Induk dan Anak Kambing Masa Pra –
Sapih. Sumatera Utara: Loka Penelitian Kambing Potong Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan.
Hinch, Geoff N and Justin J. Lynch. 1993. Comfortable Quarters for Sheep and Goats.
Australia: University Of New England.
Manus, Concepta Mc. 2011. The challenge of sheep farming in the tropics: aspects related
to heattolerance. Revista Brasileira de Zootecnia.,v.40, p.107-120.
Rook JS, Scholman G, Wing-Proctor S and Shea M. 1990. Diagnosis and control of
neonatal losses in sheep. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice
6: 531-652.
Simms, R. H. Respiration Rate and Rectal Temperature in the Newborn Lamb. Journal of
Animal Science. 1971, 32:296-300. J ANIM SCI.
Smith, J. B. & S. Mangkoewidjojo. 1988. Pemeliharaan, Pembiakan, dan Penggunaan
Hewan Percobaan di Daerah Tropis. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
44
Whittier, Dee. Keys to Successful Lambing Season. Blacksburg: Departement of large
animal clinical sciences. VA 2401-0442
Widiyono, Irkham, et al,. 2003. Frekuensi Nafas, Pulsus, dan Gerak Rumen serta Suhu
Tubuh pada Kambing Peranakan Ettawa selama 3 bulan Pertama Kehidupan Pasca
Lahir. Yogyakarta : Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.
Widyaningsih dan Yuni Nurdiani. 2000. Kiat Menekan Kematian Anak Kambing dan
Domba Periode Pra Sapih. Bogor : Balai Penelitian Ternak.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
45
”CURCUMAX” REAGEN PRAKTIS PENGUJI KANDUNGAN BORAKS PADA
BAKSO
Muhammad Arifin, Aris EkaWijaya, Andyta Septi K, Rina Irmayanti L, Erna Dwi
Astuti
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
ABSTRACT
One of food safety requirements is should be free from hazardous materials. However, there
was a lot of abuse of dangerous chemicals such as borax as a preservative or to improve food
texture. Borax can cause several problems such as impaired concentration, emotional,
aggravate autistic symptoms, nausea, vomiting, and cancer if it taken for long period. The
absence of rapid detection for borax that applicable in the field led the use of borax in food
still difficult to be controlled. Thereby, food field needs practical borax testing equipment,
easy to use, and has high sensitivity to directly detect the presence of boron.Preliminary
studies conducted to find the right combination of reagents. Reagents were HCl, polyinyl
alcohol (PVA), and turmeric solution. The reagents referred to as "Curcumax". Having found
the exact composition, reagents tested in meatballs containing borax. Borax concentration
were in meatballs are 0.25%, 0.375%, 0.5%, 0.75%, 0.875%, and 1%. Five grams of
meatballs was extracted with 10 ml of ethanol. After that, 1 ml of extract was taken and then
etched with 1 ml "Curcumax" reagent. This reagent was also compared with existing tests that
used turmeric paper.Data analysis showed no significant difference (P <0.05) between the
test used "Curcumax" with turmeric paper. However, the "Curcumax" has several advantages
compared to turmeric paper such as more easily to use with simplified procedure. The
"Curcumax" reagent do not use concentrated HCl as a hazardous material. As results, testing
could be performed directly on the field and the interpretation of testing with "Curcumax"
faster than with turmeric paper. The interpretation have already seen in less than 3 seconds,
while tumeric paper takes about 2 minutes.
Keywords: Curcumax, turmeric paper, borax test, HCl, polyvinyl alcohol (PVA), turmeric
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
46
PENDAHULUAN
Makanan yang baik harus mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh dan
memenuhi syarat keamanan. Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda-benda
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu
masalah keamanan pangan di Indonesia adalah masih rendahnya pengetahuan, keterampilan,
dan tanggung jawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan, terutama pada
industri kecil atau industri rumah tangga (Sugiyatmi, 2006; Rahayu, 2008).
Penelitian yang dilakukan suatu lembaga studi di daerah Jakarta Timur
mengungkapkan bahwa jenis jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak sekolah adalah
lontong, otak-otak, tahu goreng, mie bakso dengan saus, ketan uli, es sirop, dan cilok.
Berdasarkan uji laboratorium, pada otak-otak dan bakso ditemukan senyawa boraks
(Judarwanto, 2006).
Boraks atau yang lazim disebut asam borat (boric acid) adalah senyawa kimia turunan
dari logam berat boron (B). Boraks diperdagangkan dalam bentuk balok padat, kristal, tepung
berwarna putih kekuningan atau cairan tidak berwarna (Sugiyatmi, 2006). Boraks sudah
digunakan orang sejak lama sebagai zat pembersih, zat pengawet makanan, dan untuk
penyamak kulit. Boraks juga dapat digunakan sebagai antiseptik dan pembunuh kuman
sehingga banyak digunakan sebagai anti jamur, bahan pengawet kayu, dan bahan antiseptik
pada kosmetik. Boraks juga digunakan sebagai insektisida dengan mencampurkannya dalam
gula untuk membunuh semut, kecoa, dan lalat (Sugiyatmi, 2006).
Boraks dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik yang dalam
jangka panjang dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker, tumor, gangguan tidur,
gangguan konsentrasi, gangguan emosi, hiperaktif dan memperberat gejala pada penderita
autism pada manusia. Pengaruh jangka pendek penggunaan boraks dalam makanan dapat
menimbulkan gelaja-gejala yang sangat umum seperti pusing, mual, muntah, diare atau
bahkan kesulitan buang air besar (Judarwanto, 2006, Rahayu, 2008). Boraks juga
menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernapasan (Pongsavee, 2009).
Belum adanya alat pendeteksi boraks yang cepat dan praktis membuat kontrol
terhadap produk pangan masih terbatas. Deteksi boraks dengan kertas kunyit yang ada
sekarang belum praktis karena membutuhkan prosedur laboratorium yang cukup rumit
(Anonim, 2009). Kondisi tersebut membutuhkan usaha pengembangan alat pendeteksi yang
mudah digunakan, praktis, dan cepat untuk mengetahui adanya kandungan boraks dalam
produk pangan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
47
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alat pendeteksi boraks pada bakso yang
praktis dan mudah digunakan serta memiliki sensitivitas yang tinggi. Alat pendeteksi ini dapat
meningkatkan jaminan keamanan konsumen dan kesehatan masyarakat terkait keamanan
produk pangan. Selain itu, dapat menjadi artikel atau publikasi ilmiah.
MATERI DAN METODE
Penelitian ini merupakan modifikasi dari pengujian boraks sebelumnya yang
menggunakan kertas kunyit sebagai medianya. Pengujian boraks dengan kertas kunyit harus
melalui prosedur yang cukup rumit dan menggunakan bahan yang berbahaya yaitu HCl pekat
sehingga kurang praktis dan aplikatif.
Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menemukan kombinasi reagen yang tepat.
Reagen yang digunakan adalah HCL, polyinyl alcohol (PVA), dan larutan kunyit. Reagen
tersebut selanjutnya disebut dengan reagen “Curcumax”. Setelah ditemukan komposisi yang
tepat, reagen kemudian diujikan pada bakso yang mengandung boraks. Konsentrasi boraks
dalam bakso yang digunakan adalah 0, 0,25%, 0,375%, 0,5%, 0,75%, 0,875%, dan 1%. Lima
gram bakso diekstrak dengan 10 ml etanol. Setelah itu, diambil 1 ml ekstrak kemudian ditetesi
1 ml reagen “Curcumax”.
Tahap I: Mencari komposisi “Curcumax”.
Pada tahap ini dilakukan pencarian komposisi kandungan reagen yang tepat. Reagen
terdiri dari HCl, PVA, dan larutan kunyit.
Tahap II: Pengujian kepekaan atau sensitivitas reagen.
1. Rancangan percobaan ini menggunakan pola faktorial dengan dua perlakuan konsentrasi
boraks dan alat uji. Rancangan yang digunakan secara lengkap seperti terlihat dalam tabel
di bawah.
Konsentrasi
Boraks Ulangan
Hasil Uji (%)
Curcumax Kertas Kunyit
0 ppm
I
II
III
2500 ppm I
II
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
48
III
Dst...
10000 ppm I
II
III
2. Setiap ulangan terdiri dari 5 butir bakso yang dibuat dari 1 adonan.
3. Pengujian kandungan boraks
a. Sebanyak 5 gram bakso dicincang dan dihaluskan kemudian diekstrak dengan 10
ml etanol.
b. Sebanyak 1 ml ekstrak bakso ditetesi reagen “Curcumax” 1 ml kemudian dilihat
perubahan warna yang terjadi. Pada bakso boraks akan memperlihatkan warna
ekstak kemerahan dan pada bakso nonboraks warna ekstrak tetap kuning.
c. Pengujian dengan kertas kunyit dilakukan dengan mengekstrak 25 gram bakso
dengan 50 ml aquadest. Ekstrak tersebut ditambah dengan HCl pekat 0,7 ml
kemudian divortex. Setelah itu, kertas kunyit dimasukkan kemudian diangkat dan
dikeringkan. Setelah kering dilihat perubahan warnanya. Pada bakso boraks, kertas
kunyit akan berubah warna menjadi kemerahan sedangkan pada bakso nonboraks
kertas kunyit tetap berwarna kuning.
d. Jumlah hasil pengujian setiap ulangan dinyatakan dalam % dan dicatat untuk
dianalisis.
4. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS dan bila terdapat perbedaan
dilanjutkan dengan Tukey test.
5.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi “Curcumax”
Dari beberapa percobaan yang dilakukan didapatkan komposisi reagen yang paling
sensitif yaitu HCl:PVA:Larutan kunyit = 1:7:2. Perbandingan ini merupakan perbandingan
reagen yang paling sensitif dibanding yang lain. Komposisi dengan perbandingan ini
merupakan penemuan baru sehingga berpotensi mendapatkan hak paten.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
49
Gambar 1. Beberapa hasil percobaan dengan beberapa perbandingan komposisi reagen
Dari hasi percobaan diketahui bahwa perbandingan HCl:PVA:Larutan kunyit = 1:7:2
menghasilkan interpretasi yang paling jelas yaitu berwarna lebih merah dengan yang disertai
dengan jendalan. Oleh karena itu, komposisi reagen dengan perbandingan inilah yang kami
gunakan.
Pengujian Sensitivitas Reagen
Hasil pengujian berdasarkan interpretasi perubahan warna yang terjadi. Analisis data
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P<0,05) antara pengujian dengan reagen
”Curcumax” dengan kertas kunyit. Hal ini menunjukkan bahwa reagen “Curcumax” layak
disejajarkan dengan pengujian boraks yang lain slah satunya pengujian dengan kertas kunyit.
Walaupun begitu, reagen ”Curcumax” memiliki kelebihan dibanding kertas kunyit.
Keunggulan yang pertama, pengujian dengan reagen ”Curcumax” lebih mudah dilakukan
dengan prosedur yang lebih sederhana seperti dijelaskan dalam metode penelitian di atas.
Yang kedua, reagen ”Curcumax” tidak menggunakan HCl pekat sehingga pengujian dapat
langsung dilakukan di lapangan tanpa harus dibawa ke laboratorium terlebih dahulu.
Penggunaan HCl di lapangan sangat berbahaya. HCl merupakan bahan kimia yang berbahaya
dan bersifat membakar sehingga penggunaannya memelukan prosedur khusus. Gas yang
menguap dari HCl juga berbahaya bila mengenai mata atau terhirup. Yang ketiga, interpretasi
pengujian dengan reagen ”Curcumax” lebih cepat dibandingkan dengan kertas kunyit. Dalam
waktu kurang lebih 3 detik interpretasi sudah dapat terlihat. Berbeda dengan kertas kunyit
yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk melihat hasil interpretasinya. Berikut
tabel sensitivitas pengujian kandungan boraks dalam bakso.
Tabel perbandingan presentase hasil uji positif (%) kandungan boraks dalam bakso
menggunakan “Curcumax” dan kertas kunyit.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
50
Konsentrasi
Boraks dalam Bakso
(%)
Persentase Hasil Uji Positif (%)
Curcumax Kertas Kunyit
0 0 0
0,25 0,67 0,67
0,375 0,2 0,67
0,5 0,53 0,87
0,75 0,87 0,8
0,875 1 0,73
1 1 1
Pembahasan
Curcumin adalah pigmen alami yang berwarna kuning yang ditemukan di akar spesies
curcuma. Rosocyanine dapat terbentuk ketika terjadi reaksi antara curcumin dan boraks
sehingga menyebabkan warna coklat kemerahan pada produk pangan yang mengandung
boraks. PVA akan bereaksi dengan boraks yang ada dalam produk pangan dan membentuk
massa yang liat. PVA juga dapat mencegah kerusakan kunyit (curcumin) oleh HCl.
Gambar 3. Merupakan struktur kimia PVA setelah bereaksi dengan boraks. Crosslinked
polyvinyl alcohol gel (Katz, 2005).
Asam klorida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk menguraikan senyawa
organik. Dalam uji boraks dalam bakso, HCl berfungsi untuk memisahkan senyawa boraks
dan bahan-bahan organik di dalam ekstrak daging. Saat boraks terpisah dengan ekstrak
daging, boraks akan segera teridentifikasi oleh kombinasi PVA dan kurkumin.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
51
KESIMPULAN
Curcumax dapat digunakan sebagai reagen penguji kandungan boraks dalam bakso yang
praktis, mudah digunakan di lapangan. Reagen “Curcumax” dapat mendeteksi kandungan
boraks pada bakso sampai 25 ppm,
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2011. Rosocyanine. http://en.wikipedia.org/w/index.php. Diakses tanggal 22
September 2011.
Brockman, R. P., Audette, R. J., and Gray, M. 1985. Borax Toxicity. Can Vet J 1985, 147.
CHM107-Lab. 2004. Experiment #14: Polymers.
http://www.chemistryland.com/CHM107Lab/Lab7/Slime/Lab7Slime.htm. Diakses
tanggal 9 Oktober 2011.
Gormley, P. 2010. Polyvinyl Alcohol Slime. http://chem.lapeer.org/Chem1Docs/
SlimeDemo.html. Diakses tanggal 9 Oktober 2011.
Judarwanto, W. 2006. Perilaku Makan Anak Sekolah. Jakarta. halm 2-3
Katz, D. A. 2005. PVA Slime. www.chymist.com/PVA%20Slime.pdf
Murray, F. J. 1995. A Human Health Risk Assesssment of Boron (Boric Acid and Borax) in
Drinking Water. Regul Toxicol Pharmacol 1995, 22:221-230.
Pongsavee, M. 2009. Effect of Borax on Immune Cell Proliferation and Sister Chromatid
Exchange in Human Chromosome. Journal of Occupational Medicine and Toxicology
2009, 4: 27.
Rahayu, S. N. 2008. Profil Food Safety Knowlede And Practice Unit-Unit Rumah Tangga
Dikabupaten Sleman. jurnal penelitian halmn 2-5. Yogyakarta.
Sugiyatmi. S. 2006. Analisis Faktor-Faktor Risiko Pencemaran Bahan Toksik Boraks Dan
Pewarna Pada Makanan Jajanan Tradisional Yang Dijual Di Pasar-Pasar Kota
Semarang Tahun 2006. thesis. Undip. Semarang.
The Nuffield Foundation and Royal Society of Chemistry. 2011. PVA polymer
slime.http://www.practicalchemistry.org/experiments/pva-polymer-slime,153,EX.html.
Diakses tanggal 9 Oktober 2011.
Winneke, O. 2007. Makanan Sehat, Bebas Formalin dan Boraks,
http://www.detikfood.com/read/2006/01/05/075028/512862/291/makanan-sehat-
bebas-formalin-dan-borax. Diakses tanggal 9 Oktober 2011.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
53
PENINGKATAN FERTILITAS TELUR PERSILANGAN AYAM ISA BROWN Dan
AYAM BANGKOKDENGAN METODE INSEMINASI BUATAN
F. Rizki; Fidiyanti; F. Ekaningrum; M. Triatun; A. S. Dani
Prodi Kesehatan Hewan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
ABSTRACT
Field work on improving the day old chick production of local super strain crossing Isa brown
and Bangkok with artificial insemination method has obtaining that quality of DOC can be
shorten the productive. Prior to artificial insemination, Isa Brown chickens were selected first
and Bangkok, Bangkok to use chicken that has been aged for 6 months and Isa Brown chickens
aged 17 weeks. Then the sperm retrieval done by two people with the sort order on the wing
and tail of the sperm to be collected in a test tube. At a practice for 7 rooster sperm produced
as many as 3 ml. Before the first cement is used diluted with physiological saline in the ratio
1:6. Injecting the sperm on Isa brown chickens by intra utherine done by opening the cloaca
and the sperm is injected deep as 2 cm with the ends spliced SPET with a small hose as much
as 0,1 cc. Artificial inseminated hens as many as 177 head of 13 cages with the sum / average
home-rata10-16chickens.Eggs produced perday 112 grains of the fertile eggs pengandlingan
reached 93 eggs, if fertile eggs that made the percentage has reached 83%.
Keywordss : artificial insemination, Bangkok chicken, Isa brown chicken
PENDAHULUAN
Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor
pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang
terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata-rata pendapatan
penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Besarnya potensi sumberdaya alam yang
dimiliki, Indonesia memungkinkan pengembangan sub sektor peternakan menjadi sumber
pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.
Ayam Isa brown merupakan strain ayam ras yang diciptakan di Inggris pada tahun
1972. Strain ini diciptakan untuk memenuhi keunggulan standar yang diinginkan para
konsumen yang meliputi faktor-faktor: produktivitas dan bobot telur tinggi, konversi pakan
rendah, kekebalan dan daya hidup tinggi dan masa bertelur panjang (long lay). Namun dari
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
54
semua kriteria tadi ayam Isa brown dapat memenuhi faktor memproduksi telur yang cukup
tinggi dan harga afkirannya pun lumayan (Sudarmono, 2003).
Sudah sejak lama Ayam Bangkok dikenal dan digemari orang terutama pecinta ayam
di Indonesia. Ayam Bangkok dikenal sebagai ayam aduan yang gagah berani. Memang ayam
bangkok bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Bangkok, Thailand. Ayam-
ayam Bangkok yang beredar di Indonesia merupakan blasteran antara ayam kampung lokal
unggul dengan Bangkok murni .Ayam Bangkok dikembangbiakan memerlukan suatu
kreativitas dan ketekunan. Apalagi bila hendak menyilangkan antara ayam Bangkok dengan
berbagai jenis ayam unggul untuk bisa mendapatkan jenis ayam baru dari hasil persilangan itu
(Agus Irawan, 1996).
Berdasarkan data dari Statistik Peternakan tahun 2007 dan data Tim P2SDS Ditjen
Peternakan kebutuhan akan telur dari Ayam ras petelur meningkat dari tahun 2008 hingga
2010. Jumlah peningkatan kebutuhan telur tersebut dapat dilihat berdasar table berikut:
Kebutuhan Telur
(Ribu Ton
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
Ayam Ras Petelur 934,3
1.009,2 1.076
(Ditjennak,2008)
Semakin meningkatnya kebutuhan akan telur dari ayam ras diperlukan teknologi usaha
peternakan yang tepat guna untuk petani salah satu diantaranya dengan metode Inseminasi
Buatan. Cara ini mampu meningkatkan tingkat fertilisasi pada telur sehingga akan
meningkatkan produksi Ayam DOC(Deptan, 1998) .
Perkawinan ayam dapat dilakukan dengan sistem alami (Intra vagina) dan sistem
inseminasi buatan (Intra utherina). Pada perkawinan dengan sistem inseminasi buatan
biasanya dilakukan untuk ayam-ayam yang dipelihara dengan kandang sistem baterai/cage.
Pada prinsipnya, teknik inseminasi buatan pada ayam adalah usaha memasukkan semen ke
dalam saluran reproduksi ayam betina dengan bantuan manusia untuk menghasilkan telur
tetas. Berikut komparasi penerapan inseminasi buatan dengan kawin alami pada ayam.
Sistem Inseminasi Buatan Sistem Kawin Alami
1 ekor pejantan bias untuk 25 ekor betina 1 ekor pejantan untuk 1 ekor betina
Dapat dilakukan pada ayam yang
dikandangkan dengan sistem baterai sehingga
menghemat tempat
Dilakukan pada tempat yang luas
Mudah mengafkir ayam betina/jantan bibit Sulit mengafkir ayam betina/jantan bibit yang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
55
yang tidak potensial.
tidak potensial
(Santosa,1999).
MATERI DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ayam Isa brown, Ayam Bangkok,
NaCl Fisiologis, dan es batu. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, tabung ependorft,
spuit tanpa jarum dan termos es, selang, syringe dan mikropipet.
Tahap persiapan
Dilakukan untuk memilah ayam pejantan dan betina serta sanitasi alat dan bahan yang
digunakan untuk melakukan inseminasi buatan. Kriteria untuk ayam jantan harus sehat dan
berumur lebih dari 6 bulan sedang untuk ayam betina pada umur 17 minggu karena pada umur
tersebut ia telah mencapai kedewasaan kelamin.
Cara pengambilan Sperma/Semen
Satu pelaksana teknis duduk memegang ayam dan kedua pahanya mengempit kedua
kaki ayam. Pemijatan dilakukan dari arah punggung ke bagian ekor ayam untuk merangsang
ayam jantan. Pemencetan pada daerah kloaka dan penekanan bagian perut ayam bagian bawah
kloaka akan mengeluarkan semen ayam jantan (Titik S,1999). Pelaksana teknis yang lain
memegang tabung reaksi dan secepatnya menyorongkan tabung tadi di kloaka sewaktu kloaka
dipencet orang pertama. Ayam jantan yang sering diambil spermanya akan semakin terlatih
dan semakin mudah untuk dirangsang dalam mengeluarkan sperma. Frekuensi pengambilan
sperma 1 minggu 5 kali (3 hari berturut-turut kemudian selang 1 hari tidak diambil).
Gambar1.Pengambilan sperma
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
56
Penyimpanan Semen/ Sperma
Semen yang diperoleh dari pengumpulan dapat langsung diinseminasikan pada ayam
betina. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sebaiknya semen tidak lebih dari 30 menit
sejak pengumpulan sampai dengan diinseminasikan (semen ditampung dalam termos es
dengan suhu kurang lebih 15 °C supaya daya hidupnya tetap tinggi). Namun untuk kasus-
kasus tertentu bila tidak langsung diinseminasikan ke ayam betina, maka semen disimpan dulu
beberapa hari pada suhu 10 °C. Semen yang akan digunakan maka diencerkan terlebih dahulu
dengan NaCl 1,025 % pada pH 7,0-8,0 ditambahkan antibiotik streptomisin 200-400 mg/ml.
Perbandingan antara semen dengan NaCl 1:3. Penambahan fruktosa tepat sebelum inseminasi
dengan perbandingan fruktosa\semen 1:1 akan mempertahankan hidup sperma.(Hari
Santosa,1999).
Gambar2. Pengenceran sperma
Inseminasi pada Ayam Betina
Inseminasi buatan pada ayam betina sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Pelaksana
teknis menjepit ayam di bawah ketiak tangan kanan sambil memegang kedua kaki ayam.
Tangan kirinya memegang ekor ayam sambil menariknya ke arah atas sehingga kloaka akan
tampak jelas. Pelaksana teknis yang lain menekan bagian perut yang lunak di bawah kloaka
dengan tangan kirinya sehingga saluran semakin mudah menonjol ke luar. Kemudian dengan
syringe (alat suntik dari plastik tanpa jarum) yang kapasitasnya 0,5 cc (kecil,panjang), semen
sebanyak 0,1 cc dimasukkan ke dalam saluran telur sedalam kurang lebih 2 cm. Inseminasi
ulangan dapat dilakukan dengan interval 1 minggu atau sebanyak 0,05 cc semen dimasukkan
dengan interval AI (artificial insemination) ulangan 3 hari. Inseminasi buatan paling baik
dikerjakan pada sore hari yaitu 4 jam sebelum ayam betina melepaskan kuning telurnya atau 1
jam sesudah bertelur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pengambilan sperma pada ayam Bangkok didapatkan 3 ml sperma dari 7 ekor.
Tapi hasil ini tidak selalu konstan tergantung produksi sperma pada ayam masing-masing
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
57
perharinya. Produksi sperma dapat dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi:
umur,ransum,pakan, suhu lingkungan dan strain ayam pejantan. Sperma yang diambil bersih
tanpa ada campuran darah dan kotoran ayam. Lalu sperma yang telah ditampung dapat
disimpan terlebih dahulu pada termos es agar semen tetap hidup.
Gambar 3. Cara pengambilan sperma pada Ayam Bangkok
Sebelum diinseminasikan sperma diencerkan terlebih dahulu agar kualitasnya tidak
berkurang, 3 ml sperma diencerkan dengan NaCl fisiologis sebanyak 18 ml, sehingga didapat
21 ml semen yang siap digunakan. Pengenceran disini dimaksudkan untuk dapat
mempertahankan keadaan sperma agar kualitasnya tidak berkurang bukan untuk
memperbanyak volume dari semen itu sendiri. Pencampuran semen dengan NaCl fisiologis
dilakukan dengan membentuk angka 8 agar tidak terdapat buih. Lalu semen ditaruh dalam
termos es agar agar sperma tidak mati. Sperma yang telah diencerkan tadi dimasukkan dalam
tabung ependorf sehingga mudah untuk menggambilnya, 1 tabung ependorf dapat digunakan
untuk 1 kandang dengan jumlah ayam 10 ekor.
Semen-semen tadi disuntikan pada ayam betina yang berjumlah 179 ekor. Untuk
perekornya disuntikkan 0,1 cc semen sedalam 2 cm. Untuk melakukan inseminasi ini
dilakukan waktu sekitar 1 jam. Inseminasi dilakukan setiap hari Senin kemudian inseminasi
pengulangan dilakukan pada hari Kamis.
Gambar 4. Penyuntikan sperma pada Ayam Isa brown
Perbandingan produksi ayam yang dilakukan inseminasi buatan dengan yang tidak
dilakukan inseminasi dapat diliat berdasar grafik berikut
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
58
Gambar 5. Grafik perbandingan produksi ayam yang di IB dan tidak dilakukan IB
Berdasarkan grafik umur ayam pada waktu produktif (umur 18 minggu) tampak pada
ayam yang dilakukan inseminasi buatan dapat menghasilkan telur yang lebih tinggi sampai
pada umur 30 minggu dibanding ayam yang tidak dilakukan inseminasi buatan. Setelah lebih
dari umur 30 minggu produksi telur yang dihasilkan akan konstan sampai umur 50 minggu,
baik pada ayam yang diberi perlakuan atau tidak tapi produksi tetap lebih tinggi pada ayam
yang diinseminasi buatan.
Berikut grafik jumlah ayam dan telur yang dihasilkan perkandang di Farm
Gambar 6.Grafik jumlah ayam dan telur yang dihasilkan perkandang
Dari 179 ekor betina yang diinseminasikan rata-rata telur yang dihasilkan perkandang
berjumlah 8-9 butir telur/hari. Kemudian untuk mengetahui telur yang fertil dilakukan dengan
proses candling/peneropongan pada kamar gelap dengan box yang telah diberi lampu atau
dengan cara lain yaitu pada hari pertama telur dipecah lalu dilihat secara visual ada bentukan
seperti bintik putih. Telur fertil merupakan telur yang telah terbuahi. Dari 112 butir telur yang
dihasilkan sebanyak 93 telur mengalami fertilisasi, jika dibuat presentase sebanyak 83 % telur
telah fertil . Telur yang fertil tadi siap dimasukkan dalam mesin pengeraman untuk ditetaskan
menjadi Ayam DOC Kampung Super.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 3 5 7 9 1113U
mu
r ay
am d
alam
min
ggu
Ayam yang di IB Umur
Ayam yang di IB Produksi
Ayam yang tidak di IB Umur
0
50
1 3 5 7 9 11 13
Kandang
Jumlah ayam
Rata-rata telur /hari
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
59
KESIMPULAN
Berdasarkan dari praktek lapangan yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa
untuk dapat memproduksi DOC Ayam Kampung Super yang tinggi dapat dilakukan dengan
inseminasi buatan. Terbukti dari 112 butir telur yang dihasilkan sebanyak 93 butir telur fertil
dan siap dieramkan untuk menjadi DOC Ayam Kampung Super. Diharapkan hasil dari
praktek lapangan yang telah dilakukan ini mampu mensejahterakan peternak maupun petani
dan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan ide-ide lain mengenai bab ini. sehingga
dapat mencapai wasembada pangan sehat melalui telur.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional. 2005. SNI 01-4868.2-2005. Bibit niaga (final stock) ayam ras
tipe petelur umur sehari (kuri/doc). Badan Standardisasi Nasional Jakarta
Departemen Peternakan.1998.Inseminasi Pada Ayam Buras. Jakarta:Pustaka Litbang
Direktorat Jenderal Pertanian dan Peternakan.2008.Road Map Perbibitan Ternak.Dijernak,
Jakarta
Irawan, Agus. 1996. Budidaya Ayam-ayam Unggulan. Solo: Cv Aneka. Hlm 28,35
Santosa,Haridan Sudaryani.1999. Pembibitan Ayam Buras. Jakarta:Penebar Swadaya.Hlm 50-
59
Sastrodihardjo, S. & H. Resnawati. 1999. Inseminasi Ayam Buras Meningkatkan Produksi
Telur Mendukung Pengadaan DOC Unggul. Jakarta :Penebar Swadaya
Sudarmono, Drs.AS.2003.Pedoman Pembibitan Ayam Ras Petelur.Yogyakarta: Penerbit
Kanisius.Hlm 10,13-14,20
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
61
„BALET‟ (BELALANG NUGGET BERPROTEIN TINGGI) SEBAGAI ALTERNATIF
PEMENUHAN PROTEIN HEWANI MASYARAKAT
Ridho Andika Putra1, Anti Ahsanti
2, Muhammad Rizki Adrian
2, Muhammad Fikri
2,
Azizatul Ulfa3
1Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
3Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
ABSTRACT
Berdasarkan data United NationsDevelopment Programme (UNDP), tahun 2009 Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik tipis dari 0,728 di tahun 2007 menjadi 0,734.
Angka di tahun 2007 tersebut menempatkan Indonesia pada ranking ke 111 dari 182 negara
yang terdata. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti
Singapura (23), Brunei Darussalam (30), Malaysia (66),Thailand (87), dan Filipina (105).
Pola konsumsi atau keseimbangan kontribusi di antara jenis pangan yang dikonsumsi menjadi
salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas SDM. Dalam jangka panjang,
kekurangan konsumsi pangan dari sisi kuantitas dan kualitas(terutama pada anak balita) akan
memberi dampak negatif terhadap kualitas SDM. Kecukupan energi dan protein dapat
digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat serta keberhasilan
pemerintah dalam pembangunan pangan,pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat
secara terintegrasi. Derajat ketahanan pangan rumah tangga secara sederhana dapat ditentukan
dengan mengevaluasi asupan energi dan protein rumah tangga tersebut.Jumlah penduduk
Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta
(14,15 persen). Belalang nugget merupakan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah pada
belalang menjadi produk olahan kaya protein sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan protein
hewani masyarakat. Selain itu, belalang nugget dapat mengembangkan potensi lokal di
Indonesia.
Keywords: Balet, Belalang, Protein
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
62
PENDAHULUAN
Sampai saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, masih dihadapkan pada
masalah kualitas SDM yang rendah, yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP) IPM
Indonesia di Tahun 2009 indonesia naik tipis dari 0,728 tahun 2007 menjadi 0,734 pada 2009.
IPM yang dibuat dengan mengacu data-data pembangunan manusia tahun 2007 itu
menempatkan Indonesia pada ranking ke 111 dari 182 negara yang terdata. Hal ini berada
jauh di bawah negara-negara di Asia tenggara lain seperti Singapura yang berada di peringkat
23,Brunei Darussalam (30), Malaysia (66), Thailand (87), dan Filipina yang berada di
peringkat 105 bahkan Srilanka (102) (Anonim, 2009).
Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumber daya manusia.
Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu wilayah belum dapat
digunakan sebagai jaminan akan terhindarnya penduduk dari masalah pangan dan gizi. Hal
tersebut dikarenakan aspek pola konsumsi atau keseimbangan kontribusi di antara jenis
pangan yang dikonsumsi juga diperhatikan. Dalam jangka panjang kekurangan konsumsi
pangan dari sisi jumlah dan kualitas (terutama pada anak balita ) akan berpengaruh terhadap
kualitas SDM. Dalam hal ini, kecukupan energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator
untuk melihat kondisi gizi masyarakat, dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan
pangan, pertanian, kesehatan,dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Derajat ketahanan
pangan rumah tangga secara sederhana dapat ditentukan dengan mengevaluasi asupan energi
dan protein rumah tangga tersebut.
Fakta menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan di Indonesia) pada tahun 2011 sebesar 30,018 juta (12,49 persen) (Anonim,
2012). Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar (15.72%
menurut data BPS 2012) penduduk miskin, dapat mengindikasikan bahwa pola makan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein masih sangat rendah, ditambah
lagi dengan lemahnya daya beli masyarakat terhadap produk pangan hewani karena
ketidakmampuan kondisi ekonomi. Produk pangan hewani kita yaitu daging, susu, telur, dan
ikan, belum menggembirakan. Padahal pemerintah menargetkan swasembada daging pada
tahun 2010. Mahalnya harga sapi import dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi
penyebab tidak berkembangnya usaha ternak. Padahal, jika hanya mengandalkan produksi
peternakan rakyat, sulit bagi kita untuk swasembada on trend dengan tingkat impor 8,5%.
Saat ini 28% daging sapi masih impor. Kondisi seperti ini akan memperparah pemenuhan
asupan protein masyarakat terutama masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
63
Oleh karena itu peningkatan konsumsi protein perlu digalakkan untuk dapat
mencukupi asupan protein masyarakat miskin, salah satunya melalui penganekaragaman
pangan berprotein tinggi. Penganekaragaman pangan berprotein tinggi dapat dikembangkan
dengan menggali potensi lokal yang ada di Indonesia, yaitu dengan pengolahan belalang.
Sebagian masyarakat Indonesia tentu tidak asing lagi dengan makanan ini, di Gunungkidul
misalnya, masyarakat memenuhi kebutuhan proteinnya dengan mengkonsumsi belalang.
Selain harganya terjangkau, belalang sangat mudah didapatkan pada musim-musim tertentu.
Salah satu produk olahan yang dapat dikembangakan dengan bahan dasar belalang adalah
belalang nugget.
MATERI DAN METODE
Belalang memiliki komposisi gizi per 100 gram bagian tubuh yang dapat dimakan antara lain:
Energy Kandungan air Protein Lemak Karbohidrat Serat
Belalang
mentah
170 kkal 62,7 % 26.8% 3.8% 5.5% 2.4 %
Belalang
kering
420 kkal 7.0 % 62.2 % 10.4 % 15.8% 2.4 %
Kompenen ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan daging ayam broiler.
Berdasarkan data dari Balai Besar Industri Hasil Pertanian (1983) daging ayam broiler
mengandung protein sebesar 23,40%, lemak sebesar 1,90% dan 73,70 % air.
Berikut ini merupakan tabel kebutuhan protein per hari yang dianjurkan:
Tabel 1. Kebutuhan protein per hari
Kelompok Umur Kebutuhan protein
(g/kg berat badan)
Bayi 0 – 6 bulan
6 – 12 bulan
2,2
2,0
Anak-anak 1 – 3 tahun
4 – 6 tahun
7 – 10 tahun
1,8
1,5
1,2
Remaja 11 – 14 tahun
15 – 18 tahun
1,0
0,9
Dewasa lebih dari 19 tahun 0,9
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
64
Seiring dengan peningkatan konsumsi protein dan pengolahan belalang yang belum
berkembang, maka penyajian produk belalang dalam bentuk baru merupakan strategi untuk
meningkatkan nilai jual dari belalang.
Pokok permasalahan yang akan diselesaikan dalam momentum rencana bisnis ini
adalah pembentukan sebuah unit usaha produksi kecil dan menengah untuk produk walang
nugget. Proses pembentukan awal selalu menjadi kendala bagi pembentukan unit usaha kecil
dan menengah sehingga besar harapan kami agar program kami dapat terealisasi pada
momentum rencana bisnis ini.
Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahapan untuk mendapatkan bahan utama, bahan
tambahan serta alat yang digunakan untuk menentukan tahapan proses pembuatan belalang
nugget. Dari orientasi yang telah dilakukan diperoleh formula tepat untuk produk belalang
nugget yaitu : Alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan belalang nugget adalah: Pisau,
Telenan, Mixer, Penggiling daging, Paci pengukus, Panci, Kompor, Penggoreng, Wadah,
Pencetak nugget. Bahan. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nugget belalang di
antaranya adalah bahan utama, bahan pendukung, dan bahan analisis. Bahan Utama Bahan
utamanya adalah belalang kayu. Bahan Pendukung. Bahan pendukungnya adalah bumbu
dapur, air dan tepung tapioka, tepung panir, dan telur.
Tahap Orientasi
Pengolahanbelalang nugget di laboratorium dilakukanuntuk menentukan perlakuan
bentuk awal yang paling tepat sehingga formula awal tersebut tepat untuk diolah. Penentuan
formula untuk memperoleh standardisasi bahan sebelum diolah. Selain itu, dilakukan
observasi untuk menentukan suhu dan tekanan optimal dalam pemasakan.
Pembuatan Belalang Nugget
Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan nugget belalang ini adalah
belalang dibersihkan kemudian dikukus setengah matang. Belalang yang telah dikukus
setengah matang digiling kasar dan dilakukan pencampuran dengan bumbu yang telah
dihaluskan yaitu (bawang putih, lada garam dan penyedap rasa), tepung sagu, air, dan telur.
Kemudian dicetak dalam loyang dan dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu
ditiriskan dan dilakukan pemotongan berbentuk segi empat, lalu dilapisi dengan putih telur
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
65
dan tepung panir atau disebut breading, setelah itu digoreng dan jadilah produk belalang
nugget.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Uji Pasar
Untuk mengetahui dampak kegiatan, kami melakukan evaluasi produk melaui uji pasar.
Dan produk “Balet” Belalang Nugget kami telah mengalami uji kelayakan produk dengan
pemberian tester gratis kepada konsumen. Setelah dicoba “Balet” Belalang Nugget dapat
diterima oleh konsumen tersebut.
Produk dan Penjualan Produk
“Balet” Belalang Nugget pertama kali diproduksi yang satu bungkusnya berisi 5
potong Nugget Belalang seharga Rp. 10.000,00. Dan satu bungkusnya jika langsung digoreng
seharga Rp. 2.500,00. Kemudian terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak yang
mengakibatkan naiknya harga – harga bahan, hal ini membuat harga belalang nugget menjadi
naik dengan satu bungkusnya seharga Rp. 12.500,00 dan jika langsung digoreng dijual dengan
harga Rp. 3.000,00. Berikut adalah penjualan produk “Balet” Belalang Nugget
No Tanggal Lokasi Jumlah Harga (Rp) Total
1 21 Mei 2013 Fakultas Teknologi Pertanian UGM 10 Rp.10.000 Rp. 100.000
2 22 Mei 2013 Fakultas Teknologi Pertanian UGM 10 Rp.10.000 Rp. 100.000
2 25 Mei 2013 Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
5 Rp. 10.000 Rp. 50.000
3 2 Juni 2013 Sunday Morning UGM 80 Rp. 2.500 Rp. 200.000
4 18 Juni 2013 Direktorat Akademik UGM 180 Rp. 2.500 Rp. 450.000
5 19 Juni 2013 Direktorat Akademik UGM 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000
6 30 Juni 2013 Sunday Morning UGM 20 Rp. 3.000 Rp. 60.000
7 9 Juli 2013 Plaza Agro Gadjah Mada UGN 10 Rp. 12.500 Rp. 125.000
8 11 Juli 2013 Giripurwo Gunung Kidul 40 Rp. 12.500 Rp. 500.000
Total 1.595.000
Sosialisasi dan Pemasaran “Balet” Belalang Nugget
Media Promosi yang dijalankan yaitu melalui media online dan offline. Media online
terdiri dari Blog “Balet” Belalang Nugget http://belalangnugget.blogspot.com/. Grup
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
66
Facebook “Balet” Belalang Nugget, twitter @nuggetbelalang, e-mail
[email protected]. Sedangkan pemasaran offline dilakukan dengan menggunakan
leaflet dan poster. Belalang Nugget sudah dipasarkan di beberapa tempat pada bulan
Mei,antara lain:
1. Pameran PKM Expo Agritech Study Club FTP UGM tanggal 22 – 23 Mei 2013.
2. Rumah Nugget Pak Lazib Jalan Jogokaryan
3. Pameran Di acara Tetavarium Permateta UGM tanggal 25 Mei 2013.
4. Stand langsung di Direktorat Administrasi dan Akademika UGM tanggal 18 Juni
2013.
5. Pameran di Stand Agritech Study Club tanggal 19 Juni 2013
6. Bazar Sunday Morning UGM tanggal 10 Juni, 24 Juni dan 30 Juni 2013.
7. Asrama Mahasiswa Putri tanggal 2 Juli 2013
8. Asrama Putra PPSDMS Regional 3 Yogyakarta jalan Kaliurang KM. 8
9. Pembelian secara online dan langsung kepada konsumen.
10. Plaza Agro Gadjah Mada UGM
KESIMPULAN
Dari Program ini telah tercipta produk “Balet” Belalang Nugget berbahan baku
belalang sebagai pangan lokal fungsional. Produk ini telah berhasil memberikan peluang pasar
baru dalam rangka penganekaragaman sumber protein sebagai asupan gizi masyarakat dengan
harga yang cukup bersaing.
DAFTAR PUSTAKA
Abubakar dan Sri Usmiyati.2007. Teknologi Pengolahan Daging. Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor
Anonim. 2009. Belalang. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Belalang. diakses pada tanggal
27 September 2012 pukul 13. 34 WIB
Anonim. 2012. Jumlah Penduduk Miskin Pada Bulan Maret 2009 Sebesar 30,018 Juta (12,49
Persen). Dalam http ://www.bps.go.id. diakses pada tanggal 27 September 2012
pukul 16.34 WIB
Anonim.2009. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Naik. Dalam
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/10/98674/92/14/Indeks-
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
67
Pembangunan-Manusia-Indonesia-Naik. Diakses tanggal 27 September 2012 pukul
11.16 WIB
Kusmaryani. 2005. Protein Belalang Lebih Tinggi Dari Udang. Dalam http://www.smallcrab.com/kesehatan/25-
healthy/292-protein-belalang-lebih-tinggi-dari-udang. diakses pada tanggal 27 september 2012 pukul 13.25
WIB
Kramlich, W.E., (1973), Sausage Product, dalam J.F. Price dan B.S. Schewiger (eds), The Science of Meat and Meat Product, W.H. Freeman and Co. San Fransisco.
Muchtadi, Deddy. 1989. Evaluasi Nilai Gizi Pangan. PAU Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
Muchtadi, Deddy. 1989. Petunjuk Laboratorium Evaluasi Nilai Gizi Pangan. Bogor.IPB. Sudarmadji, Slamet dkk. Analisa Bahan Makanana dan Pertanian. PAU pangan dan gizi UGM dengan
LIBERTY,Yogyakarta.
Tanikawa., (1963), dalam Hilma Y, (1999), Pengaruh Perbandingan Penambahan Ampas Tahu dan Ikan Tongkol, UNPAS, Bandung.
Winarno, F.G.1987. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia,Jakarta.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
69
ANALISIS POTENSI KOMBINASI STIMULASI AKUPUNTUR DENGAN BEE
VENOMPADA TITIK AKUPUNTUR ST36 SEBAGAI PENDEKATAN PREVENTIF
KOMPLIKASI VASKULER PADA DIABETES MELLITUS TIPE II
Gamal1
1Universitas Brawijaya, Malang
ABSTRACT
Patients with DM have a risk two until four times higher than normal population for the
occurrence of vascular complications. This complication are responsible for the increased
mortality rate reaches 75% of deaths from DM. Vascular complications caused by Diabetes
Mellitus Type 2 (DMT2) initially began with the occurrence of insulin resistance. Insulin
resistance causes increased levels of leptin, this increase will directly increase ROS
generation due to binding of leptin to Ob-R in endothelial. Hyperglycemia also contribute to
increased production of ROS and also caused the occurrence of glycosylation reactions that
generate AGEs. Increased ROS and AGEs in DMT2 capable of damaging lipids, proteins,
DNA, and also able to stimulate activation of NF-κB. NF-κB activation would lead to
transcription of inflammatory gene in the nucleus of endothelial cells and lead to the
occurrence of vascular complications. ST36 Point or Zusanli points is acupuncture point
located at 3 inches below the edge of the inferior patella and 1 inch laterally adjacent to the
anterior crest of the tibia. Bee Venom Acupuncture at point ST36 increase antioxidants,
reducing free radicals, and reduce NF-κB. The existence of barriers against ROS by Bee
Venom Acupuncture causes downs ROS in stimulating IKK activity, thereby NF-κB activation
can be suppressed. Bee Venom Acupuncture is not only able to inhibit ROS, but also able to
inhibit the activity of MAPK and NF-κB directly, by inhibition of ROS, MAPK, and NF-κB,
the NF-κB activity on target genes will experience a down-regulation, sothat the occurrence
of complications vasculature can be inhibited.
Keywords: Vascular Complication, DM, bee-venom-acupuncture,
PENDAHULUAN
Diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif tidak menular yang semakin
meningkat jumlahnya1. Data statistik WHO (2008) menyatakan bahwa penderita diabetes di
Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000,
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
70
menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan faktor
risiko yaitu obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok, dan hiperkolesterol2. Pada tahun 2005
diketahui bahwa 1,1 juta jiwa meninggal akibat diabetes dan hampir 80% kematian dijumpai
pada negara-negara berkembang terutama di usia 45-64 tahun3.
Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik terjadinya
hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.
Hiperglikemia kronik pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang,
disfungsi, atau kegagalan beberapa organ tubuh terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan
pembuluh darah3. Diebetes mellitus tipe 2 (DMT2) merupakan 90% dari kasus DM yang ada
dan mempunyai pola familial yang kuat4,5
.
Angka kejadian dan prevalensi penyakit Diabetes Mellitus (DM), semakin lama
semakin meningkat.DM berkaitan erat dengan kelainan kardiovaskuler seperti hipertensi,
sklerosis pembuluh darah, maupun kelainan pembuluh darah mikro. Penderita DM
mempunyai risiko dua sampai empat kali lebih tinggi dibanding populasi normal untuk
timbulnya penyakit kardiovaskuler ataupun komplikasi mikro dan makro angiopati6.
Komplikasi tersebut sangat terkait dengan beratnya keadaan hiperglikemi yang ada dan ikut
bertanggung jawab terhadap peningkatan angka mortalitas yang mencapai 75% dari kematian
akibat DM7.
Terapi akupuntur merupakan salah satu bagian dari pengobatan komplementer dan
alternatif yang telah dipercaya secara ilmiah sebagai komponen yang berguna pada praktik
klinik di Asia timur. Pada praktiknya, terapi akupuntur digunakan untuk menyembuhkan
penyakit dan mempertahankan kesehatan. WHO sudah mendata lebih dari 40 indikasi
pengobatan untuk akupuntur dan National Institutes of Health telah menerima validitasdari
pengobatan akupuntur. Penelitian yang dilakukah Sam-Woong Rho menyatakan bahwa
stimulasi akupuntur berpengaruh pada aktivitas seluler, ekspresi gen, dan aktivitas
metabolisme. Studi fMRI lain pada hewan juga menunjukkan bahwa akupuntur dapat secara
langsung meningkatkan aktivitas otak, khususnya pada daerah hipotalamus (HT) 68
.
Titik ST36 adalah titik akupuntur yang disebut Zusanli. Titik ini terdapat di kaki di
bagian depan dan sedikit di bawah lutut yang biasa disebut Stomach Meridian Point #36 atau
ST36. Pengobatan akupuntur pada titik ini diketahui memperbaiki gangguan pencernaan,
anemia, kelelahan, dan kelemahan. Studi Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)
menunjukkan bahwa akupuntur pada titik ST36 yang merupakan titik akupuntur utama pada
kaki memodulasi aktivitas neural dari CNS manusia70
.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
71
"All things are poison and nothing is without poison, only the dose permits something
not to be poisonous" Paracelsus (1493-1541). Pada penemuan terbaru Bee venom
mengandung Melittin. Melittin yang sudah di buktikan dapat mensupresi NF-κB pada
proliferasi vascular smooth muscle cell (VSCM) 78
. Oleh karena itu, tujuan dari karya tulis ini
adalah untuk mengetahui potensi kombinasi stimulasi akupunturdengan Bee Venom pada titik
ST36 sebagai penatalaksanaan Penyakit Jantung Koroner pada penderita DMT2.
MATERI DAN METODE
Hiperglikemia dan resistensi insulin merupakan faktor penting dari patomekanisme
DM. Keadaan hiperglikemia pada DM akan menyebabkan peningkatan autoksidasi glukosa,
glikosilasi protein, dan jalur sorbitol (poliol) yang berpengaruh pada peningkatan
pembentukan AGEs dan ROS8. Sedangkan peningkatan produksi ROS akan menginduksi
aktivasi NF-κB akibat pelepasan IκB9. Resistensi insulin pada DM berpengaruh pada
peningkatan kadar leptin dan penurunan adiponektin serum. Adanya Ob-R pada sel endothel
menyebabkan induksi tidak langsung disfungsi endothel melalui aktivasi NF-κB akibat
stimulasi MAPK10
. Peningkatan aktivasi NF-κB baik akibat induksi leptin maupun ROS akan
menyebabkan meningkatnya respon proinflamasi dan adhesion molecules yang bertindak
dalam patomekanisme terjadinya komplikasi vaskuler pada DMT29,10
.
Pada DMT2 yang menjadi fokus permasalahan dalam terjadinya komplikasi vaskuler
adalah ROS yang bekerja sebagai perusak membran lipid sel, protein, maupun DNA. Bee
venom mengandung zat yang bernama melittin. Melittin sudah di buktikan dapat mensupresi
NF-κB pada proliferasi vascular smoothmuscle cell(VSCM). Dengan adanya supresi NF-κB
maka secara otomatis ekspresi molekul adhesi dan ekspresi enzim inflamasi pun akan
terhambat. Dengan demikian akan mencegah terjadinya komplikasi vaskuler pada DMT2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidakseimbangan Oksidan dan AntioksidanAkibat Hiperglikemi pada DMT2
Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa pada DMT2 resistensi insulin
merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Selain itu, resistensi
insulin juga menimbulkan peningkatan kadar leptin pada plasma. Adanya Ob-R pada endothel
pembuluh darah, secara langsung akan meningkatkan ikatan antara leptin dan Ob-R yang
mampu mengaktivasi MAPK. Dalam proses selanjunya aktivasi ini akan menyebabkan
peningkatan ROS di mitokondria.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
72
Keadaan hiperglikemia juga menginduksi pembentukan ROS di mitokondria dan
memicu oksidasi glukosa. Terjadinya peningkatan glikosilasi protein pada DMT2 bersama
dengan oksidasi glukosa secara bersama-sama akan menyebabkan terjadinya reaksi Maillard
(glication). Dalam reaksi ini glukosa dan protein akan saling melekat tanpa bantuan
enzimatik dan menghasilkan amodory product (1-amino, 1-deoksi, 2-ketose) sebagai produk
utama pembentuk AGEs.
Produk awal dari reaksi ini disebut Schiff base yang secara spontan akan mengalami
pembentukan kembali menjadi Amadori product. Reaksi inisial ini bersifat reversible,
tergantung pada konsentrasi dari reaktannya. Menurunnya konsentrasi glukosa akan
melepaskan ikatan glukosa dari asam amino yang diikatnya. Sedangkan tingginya konsentrasi
glukosa akan memberikan efek sebaliknya. AGEs merupakan produk yang bersifat
irreversibel. Produksi AGEs yang meningkat pada DMT2 meningkatkan risiko terjadinya
komplikasi pada DMT2.
Karakteristik dari AGEs adalah kemampuannya membentuk ikatan kovalen antar
protein, yang berakibat pada berubahnya struktur dan fungsi protein, seperti pada matriks
seluler, membran dasar, dan komponen dinding pembuluh darah. Disamping itu, AGEs
memiliki interaksi dengan cell-surface AGE-binding receptors yang berakibat pada aktivasi
molekul – molekul proinflamasi dan radikal bebas. AGEs selanjunya akan memfasilitasi
pembentukan ROS melalui perubahan struktural dan fungsi protein dari membran sel maupun
pembuluh darah. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan saling mempengaruhi antara produk
glikasi lanjut dengan pembentukan ROS, begitu pula sebaliknya.
Glukosa yang tinggi dalam plasma akan direduksi oleh aldose reductase (AR) menjadi
sorbitol. Sorbitol selanjutnya dioksidasi menjadi fruktosa dengan mereduksi NAD+ menjadi
NADH oleh sorbitol dehidrogenase (SDH). Peningkatan aktivasi jalur ini menyebabkan
meningkatnya turn over NADPH, diikuti dengan menurunnya rasio NADPH sitosol bebas
terhadap NADP+. Hal ini sangat penting karena NADPH sitosoloik juga berperan sebagai
defense antioksidan. Penurunan availability dari NADPH sitosolik berpengaruh pada
penurunan aktivitas glutathione reductase (GRD). Akibatnya terjadi kompetisi antara AR
dengan GRD yang memicu deplesi GSH, sehingga menurunkan aktivitas antioksidan endogen
dan meningkatkan produksi okigen radikal.
Resistensi insulin maupun keadaan hiperglikemia pada DMT2 pada dasarnya bersama-
sama meningkatkan produksi ROS. ROS yang berlebih dalam tubuh menimbulkan
ketidakseimbangan antara oksidan den pertahanan antioksidan endogen. Akibatnya ROS akan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
73
menyerang membran lipid, protein maupun DNA yang mengarah pada kerusakan sel dan
jaringan di dalam tubuh.
Komplikasi Vaskuler sebagai Akibat Ketidakseimbangan Oksidan dan Antioksidan
pada DMT2
Efek nagatif dari ROS tidak berakhir sampai disitu, ROS bersama-sama dengan MAPK
juga berperan sebagai stimulus pengaktivasi IKK yang memicu fosforilasi subunit IκB dari
kompleks NF-κB p50/p65 heterodimer melalui ubiquitin-proteosome system. Akibatnya,
terjadi degradasi subunit IκB oleh proteosome dan terjadi aktivasi NF-κB. NF-κB yang aktif
dengan mudah akan melakukan translokasi dari sitoplasma ke nukleus. Di dalam nukleus NF-
κB akan berikatan dengan κB-binding site pada promoter gen target dan menginduksi
terjadinya transkripsi menjadi mRNA yang selanjutnya meningkatkan ekspresi faktor-faktor
inflamasi dan molekul adhesi, seperti TNF-α, TNF- β, ICAM-1, VCAM, MCP-1, dll.
Peningkatan regulasi terhadap faktor inflamasi dan molekul adhesi akibat peningkatan
aktivitas NF-κB berhubungan dengan disfungsi endothel dan proses terjadinya inflamasi.
Kerusakan endothel menyababkan terjadinya aterosklerosis. Ini disebabakan karena endothel
yang terlepas dalam sirkulasi akan bergabung dengan platelet dan makrofag akibat stimulasi
molekul adhesi dan memicu terjadinya trombosis. Keadaan yang demikian meningkatkan
risiko terjadinya CHD sebagai komplikasi utama penyebab kematian pada DMT2.
Peningkatan Antioksidan dan Penurunan Radikal Bebas Akibat Akupuntur pada Titik
ST36
Studi melalui functional magnetic resonance imaging (fMRI) menunjukkan bahwa
akupuntur pada ST36 mampu mengubah aktivitas transkripsi dan memodulasi aktivitas neural
dari CNS manusia75
. Studi fMRI pada hewan juga menunjukkan bahwa akupuntur secara
langsung meningkatkan aktivitas otak, terutama pada bagian hipotalamus75
.Penemuan ini
menunjukkan bahwa akupuntur memodulasi berbagai fungsi otak pada hipotalamus, yang
mana hipotalamus merupakan pusat control nyeri desenden dan modulasi endokrin terhadap
imunitas.
Penelitian Liu et al dengan pengobatan akupuntur terhadap otak tikus menunjukkan
bahwa stimulasi akupuntur meningkatkan aktivitas superoxide dismutase (SOD) dan
glutathioneperoxidase (GPx), serta menurunkan produksi Reactive Oxygen Species (ROS)
pada hippocampus. Peningkatan aktivitas SOD pada HT sesuai dengan peningkatan regulasi
transkripsi gen SOD1. Untuk memastikan bahwa stimulasi akupuntur benar-benar
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
74
menurunkan produksi ROS Liu et al mengukur ROS pada LV. Ternyata ROS mengalami
penurunan secara signifikan dengan stimulasi akupuntur pada titik ST36, yaitu sebesar 28,2%
dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun ternyata stimulasi akupuntur di luar titik
ST36 tidak mengakibatkan penurunan ROS. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa
stimulasi akupuntur pada titik sembarang di tubuh tidak mengakibatkan efek yang sama
dibandingkan stimulasi pada titik spesifik ST36(Kim et al., 2005b; 2006).
Mekanisme Neuroimun Akupuntur dalam Mencegah Komplikasi Vaskuler
Aksi anti-inflamasi dari akupuntur di mediasi dari refleks inhibisi sentral dari sistem
imun innate. Bukti klinis dan laboratoris telah menunjukkan negative feedback loop antara
sistem saraf otonom dan sistem imun innate. Stimulasi akupuntur dari nervus vagus
menghambat aktivasi makrofag dan produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF, IL-1β, IL-6,
IL-18.
Akupuntur mengakibatkan aktivasi nervus vagus eferen dan deaktivasi inflamasi
makrofag. Penggunaan akupuntur sebagai terapi adjuvant terhadap terapi konvensional
berpotensi untuk menyembuhkan penyakit inflamasi kronis dan penyakit autoimun.
Gambar1. Modulasi neural dari sistem imun innate yang melibatkan proinflamasi dan anti-
inflamasi68
Eksperimen Matthay dan Ware telah menunjukkan bahwa otak dan sistem imun innate
memiliki 2 jalur, yaitu jalur humoral dan neural. Dalam hal ini, sistem imun berperan sebagai
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
75
organ sensoris untuk menginformasikan ke otak tentang terjadinya inflamasi dan kerusakan
jaringan, sedangkan otak berperan dalam membatasi dan melokalisasi respon inflamasi.
Proses ini diawali ketika unmyelinated sensory C fibers yang terdapat pada semua
organ dan jaringan melepaskan substance P dan proinflamasi lain sebagai respon terhadap
stimulus. Respon ini mengakibatkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan
leukosit marginasi.
Terjadinya inflamasi pada perifer memberikan sinyal yang dibawa lewat jalur
transmisi cepat pada nervus vagus aferen ke traktus nucleus viscerosensory pada batang otak
dan lewat jalur transmisi lambat yang melibatkan sitokin. Hal ini mengakibatkan respon akut
stress dari system nervus simpatis yang dimediasi secara langsung oleh interaksi saraf ke sel
imun atau secara tidak langsung melalui axis neuroendokrin-adrenal. Ikatan katekolamin ke
reseptor 2-adrenergic mengakibatkan menurunnya agen proinflamasi (TNF, IL-1, IL-6,
and IL-18) dan meningkatnya agen anti-inflamasi (IL-10), sehingga akan mengontrol respon
inflamasi. Signal ini juga menstimulus hipotalamus dan kompleks vagal dorsal untuk
menstimulasi pelepasan ACTH sehingga mengaktivasi jalur anti-inflamasi humoral.
Gambar 2. Aktivitas eferen pada nervus vagus68
Meskipun demikian, bukti klinik dan laboratoris menunjukkan bahwa sistem nervus
parasimpatis memainkan peran utama pada penurunan regulasi dari sintesis sitokin. Jalur
vagus yang mengintervensi system reticuloendothelial telah diketahui mampu menjaga
resting heart rate 60-80 bpm dan mengontrol aktivitas digestif dan pencernaan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
76
Matthay dan Ware juag telah mengidentifikasi ekspresi 7 nicotinic acetylcholine
receptor (7nAChR) pada jaringan makrofag dimana acetylcholine (ACh) berikatan dengan
sistem monosit-makrofag untuk menghambat sintesis pro-inflamasi. Mereka telah melaporkan
bahwa konsentrasi nanomolar dari asetilkolin cukup untuk menghambat produksi dari sitokin
pro-inflamasi pada kultur makrofag manusia yang mendapatkan lipopolysaccharide.
Mekanisme molekuler dari efek anti-inflamasi melibatkan jalur dari tyrosine kinase Jak2 dan
faktor transkripsi STAT3.
Perubahan Mikrosirkulasi sebagai Efek Akupuntur
Stimulasi akupuntur dilaporkan mampu meningkatkan mikrosirkulasi. Stimulasi
akupuntur secara langsung mampu meningkatkan diameter dan kecepatan aliran darah pada
arteriol perifer yang diakibatkan oleh stimulasi fisik, sehingga dapat berperan sebagai
pengobatan suportif untuk penyakit yang berkaitan dengan rendahnya aliran darah perifer.
Gambar 3. Perubahan diameter arteriol92.
Pada gambar 3diameter arteriol meningkat secara signifikan pada akupuntur, yaitu
131%±14%, Diameter arteriol mencapai nilai maksimal pada 20 menit setelah stimulasi
akupuntur berakhir.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
77
Gambar 4. Perubahan kecepatan aliran darah92
Pada gambar 4 kecepatan aliran darah meningkat secara signifikan menjadi
131%±14% dan 220%±66% pada akupuntur. Kecepatan aliran darah memperlihatkan
kecenderungan perubahan yang sama seperti perubahan diameter arteriol. Studi ini
menunjukkan bahwa aliran darah arteriol mulai meningkat setelah 10 menit akupuntur
dimulai, meningkat secara maksimal setelah 20 menit akupuntur berakhir, dan Efek akupuntur
bertahan 40 – 50 menit setelah stimulasi berakhir.
Gambar 5. Fotografi dari observasi pembuluh darah mikro92
Gambar5 adalah gambaran mikroskopis dari observasi pembuluh darah mikro dengan
menggunakan metode REC. Banyak penelitian yang membuktikan efek akupuntur pada
perubahan aliran dan pembuluh darah, antara lain: Maeda et al. melaporkan bahwa stimulasi
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
78
akupuntur menurunkan konsentrasi plasma endotelin 1 sehingga menyebabkan vasodilatasi
dan peningkatan temperatur kulit85
. Litscher et al menemukan bahwa akupuntur
meningkatkan stimulasi aliran darah pada arteri serebral media86
. Lie et al juga melaporkan
bahwa stimulasi elektrik dari nervus medianus memperbaiki ischemia myocardial lokal pada
kucing yang dianestesi87
. Boutouyrie et al memperlihatkan bahwa stimulasi akupuntur
menyebabkan vasodilatasi dari arteri radialis88
. Hsieh et al menemukan bahwa aliran darah
dari hipotalamus, midbrain, dan cerebellum meningkat setelah stimulasi akupuntur89
. Uchida
et al. juga menunjukan bahwa stimulasi akupuntur meningkatkan aliran darah serebrum yang
diukur dengan menggunakan flowmeter laser Doppler pada tikus yang dianestesi90
.
Loaize et al melaporkan bahwa diameter arteriol pada kapsul sendi lutut meningkat
sekitar 25% setelah stimulasi akupuntur pada otot quadriceps tikus yang dianestesi Untuk
memeriksan mekanisme dari vasodilatasi, dia mempelajari efek NO yang merupakan
vasodilator yang dilepaskan dari sel endotel dan saraf. Ternyata vasodilatasi tidak terjadi
setelah pmberian inhibitor NO, yaitu L-NAME (N-nitro-l-arginine). Penelitian ini
mengindikasikan Nitric Oxide berperan pada vasodilatasi yang disebabkan oleh stimulasi
akupuntur(Loaize at al, 2004). Tsuchiya et al mempelajari efek akupuntur terhadap kadar NO.
Kadar NO pada plasma dari lengan yang diberi akupuntur secara signifikan meningkat pada
menit ke-5 dan ke-60 setalah akupuntur. Aliran darah dari Jaringan subkutan palmar pada
lengan yang mengalami akupuntur juga meningkat. Berbagai bukti penelitian tersebut
merupakan indikasi yang kuat bahwa akupuntur mampu memperbaiki fungsi vaskuler.
Mekanisme Bee Venom dalam Mensupresi NF-κB pada DMT2
NF-κBmemicutranskripsi gen yang berhubungan dengan aterosklerosis(VCAM-1,
MCP-1, Tumor Necrosis Factor (TNF), Metaloproteinase Matriks(MMP) -9 dan faktor
jaringan procoagulant). Serangkaian kejadian ini menyebabkan akumulasi makrofag pada
dinding arteri yang yang kemudian akan membentuk foam cell. Di sisi lain NF-κB juga
meningkatakan enzim-enzim inflamasi yang juga berperan pada proses pembentukan plak
aterosklerosis.
Bee venom mengandung zat yang bernama melittin. Melittin sudah di buktikan dapat
mensupresi NF-κB pada proliferasi vascular smoothmuscle cell(VSCM). Dengan adanya
supresi NF-κB maka secara otomatis ekspresi molekul adhesi dan ekspresi enzim inflamasi
pun akan terhambat. Dengan demikian akan mencegah terjadinya komplikasi vaskuler pada
DMT2.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
79
Mekanisme Kerja Akupunturdengan Bee Venompada Titik ST36 (Zusanli) dalam
Mencegah Komplikas Vaskuler pada DMT2
Pada DMT2 yang menjadi fokus permasalahan dalam terjadinya komplikasi vaskuler
adalah ROS. ROS bekerja sebagai sebagai perusak membran lipid sel, protein, maupun DNA.
Diketahui bahwa, kombinasi akupuntur dan bee venompada titik akupuntur ST36mampu
mengakibatkan perubahan ekspresi gen di hipotalamus dan perubahan aktivitas enzim
antioksidatif. Titik ST36 atau titik Zusanli terletak pada 3 inci di bawah tepi inferior patella
dan 1 inci disebelah lateral anterior crest dari tibia(Teruo Matsumoto, 2004). Bee venom
akupunturpada titik ST36 mampu meningkatkan aktivitas superoxide dismutase, Glutatione
Peroxidase, dan menurunkan ROS.
Apabila induksi akupunturdengan bee venomtelah menghambat peningkatan ROS
pada DMT2, maka diduga bahwa terjadinya kerusakan protein dan DNA dapat dihambat.
Tidak hanya itu, dengan dihambatnya ROS melalui bee venomakupuntur, pembentukan AGEs
juga akan dapat ditekan sehingga dapat menurunkan amplifikasi pembentukan ROS oleh
AGEs.
Adanya hambatan terhadap ROS oleh akupuntur menyebabkan turunya aktivitas ROS
dalam menstimulasi IKK, dengan demikian aktivasi NF-κB dapat ditekan. Bee venom
akupunturtidak hanya mampu mengahambat ROS, namun juga mampu menghambat aktivitas
MAPK dan NF-κB secara langsung, sehingga kerja akupuntur menjadi lebih kompleks yaitu
pada radikal bebas yang terbentuk pada DMT2 dan secara genomik. Dengan hambatan pada
ROS, MAPK, dan NF-κB maka aktivitas NF-κB pada gen target akan mengalami down-
regulation dalam menghasilkan enzim inflamasi, molekul adhesi, sitokin, maupun kemokin
yang berperan terhadap disfungsi endothel dan komplikasi vaskuler.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
80
Gambar 6. Skema Usulan analisis potensi bee venom akupuntur sebagai preventif komplikasi vaskuler
pada DMT2 melalui kajian biomolekuler
KESIMPULAN
Resistensi insulin maupun keadaan hiperglikemia pada DMT2 bersama-sama
akan meningkatkan produksi ROS dan MAPK. ROS bersama-sama dengan MAPK akan
mengaktivasi NF-κB yang meningkatkan ekspresi faktor-faktor inflamasi dan molekul
adhesi, sehingga berakibat pada terjadinya komplikasi vaskuler
Akupuntur dan toksin lebah pada titik ST36dapat mencegah komplikasi vaskuler
pada Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan meningkatkan SOD, GP, dan menurunkan radikal
bebas, serta menurunkan NF-κB. Hambatan pada ROS dan NF-κB akanmengakibatkan
down-regulation enzim inflamasi, molekul adhesi, sitokin, maupun kemokin yang
berperan terhadap disfungsi endothel dan vaskuler, sehingga komplikasi vaskuler dapat
dicegah.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
81
Akupuntur dilakukan 2x seminggu selama dua bulan dengan menggunakan
jarum akupuntur yang steril dan terbuat dari stainlesssteel dengan ukuran 0,25 x 30 mm.
Jarum ditusukkan tegak lurus sedalam 2-3 mm pada ST 36 kanan dan kiri lalu diputar
sekitar 360° sebanyak 60 kali per menit selama 20 detik. Proses tersebut dimanipulasi
setiap 5 menit dan ditarik setelah 20 menit. Toksin lebah sebanyak 0,1 ml disuntikkan
pada titik akupunktur ST 36 bersamaan dengan penusukan akupuntur.
DAFTAR PUSTAKA
1. Suyono, Slamet. (2007). “Patofisiologi Diabetes Melitus” dalam Penatalaksanaan
Diabetes Melitus Terpadu. Jakarta: Pusat Diabetes dan Lipid RSUP Nasional Dr.
Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
2. Yusharmen, I Nyoman Kandun, Hariadi Wibisono, Endang R Sedyaningsih,
Widarso. 2005. New England Journal of Medicine, 355(21) : 2186-94.
3. WHO. 2008. Diabetes. (Online) (http://www.who.int/diabetes/facts/
world_figures/en/, diakses 18 September 2010)
4. Mansjoer, Arif. 2007. Kapita Selekta Kedokteran. Edisi Ketiga. Jakarta: Media
Aesculapius.
5. Price, S.A. and Wilson, L.M. 2006. Patofisiologi : Konsep Klinis Proses-proses
Penyakit (Volume 2 Edisi 6). Jakarta : EGC.
6. Beckman JA, Creager MA, Libby P. Diabetes and atherosclerosis: epidemiology,
pathophysiology, and management. JAMA, 287:2570-81, 2002
7. Gutterman D. Vascular dysfunction in hyperglycemia. Is Protein Kinase-C the
culprit. Circ Res. 90:5-7, 2002
8. Ahmed, S., E. Nawata, M. Hosokawa, Y. Domae, and T. Sakuratani. 2002.
Alterations in photosynthesis and some antioxidant enzymatic activities of
mungbean subjected to waterlogging. Plant Sci. 163: 117-123.
9. Shutenko Z, Henry Y, Pinard E, et al. 2009. Influence of antioxidant quercetin in
vivo on the level of nitric oxide determined by electron paramagnetic resonance in
rat brain during global ischemia and reperfusion. Biochem Pharmacol;57:199-208.
10. Van Acker SA, Tromp MN, Haenen GR, etal. 2005. Flavonoids as scavengers of
nitric oxide radical. Biochem Biophys Res Commun ;214:755-9.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
82
11. Guyton dan Hall. 2004. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta : EGC
12. Cines, D.B., Pollak, E.S., Buck, C.A., Loscalzo, J., Zimmerman, G.A., McEver,
R.P., Pober, J.S., Wick, T.M., Konkle, B.A., Schwartz, B.S., Barnathan, E.S.,
McCrae, K.R., Hug, B.A.Schmidt, A., and Stern, D.M. 2008. Endothelial Cells in
Physiology of Vascular Disorders. The Journal of The American Society of
Hematology, Volume 91, No. 10.
13. Noer, M.S., Waspadji, S., Rachman, A.M., Lesmana, L.A., Widodo D., Isbagio, H.,
Alwi, I. dan Husodo, U.B. 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta : Balai
Penerbit FKUI.
14. Velazquez, E., Winocour, P.H., Kesteven, P., Alberti, K.G., and Laker, M.F. 2005.
Relation of lipid peroxides to macrovascular disease in type 2
diabetes.DiabeticMedicine8, 752-758.
15. Collier, A., Rumley, A., Rumley, A.G., Paterson, J.R., Leach, J.P., Lowe, G.D., and
Small, M. 2002. Free radical activity and hemostatic factors in NIDDM patients
with and without microalbuminuria.Diabetes41, 909-913.
16. MacRury, S.M., Gordon, D., Wilson, R., Bradley, H., Gemmell, C.G., Paterson,
J.R., Rumley, A.G., and MacCuish, A.C. 2003. A comparison of different methods
of assessing free radical activity in type 2 diabetes and peripheral vascular disease.
DiabeticMedicine10, 331-335.
17. Griesmacher, A., Kindhauser, M., Andert, S.E., Schreiner, W., Toma, C., Knoebl,
P., Pietschmann, P., Prager, R., Schnack, C., and Schernthaner, G. 2005. Enhanced
serum levels of thiobarbituric-acid-reactive substancesin diabetes mellitus. Am. J.
Med. 98, 469-475.
18. Santini, S.A., Marra, G., Giardina, B., Cotroneo, P., Mordente, A., Martorana, G.E.,
Manto, A., and Ghirlanda, G. 2007. Defective plasma antioxidant defenses and
enhanced susceptibility to lipid peroxidation in uncomplicated IDDM. Diabetes46,
1853-1858.
19. Robertson, R.P. 2004. Chronic oxidative stress as a central mechanism for glucose
toxicity in pancreatic islet beta cells in diabetes, J. Biol. Chem. 279(41), 42351–
42354.
20. West, I.C., 2005. Radicals and oxidative stress in diabetes. Diabetic Med. 17, 171–
180.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
83
21. Hiramatsu, K, S. Arimori, 2008. Increased superoxide production by mononuclear
cells of patients with hypertryglycerdemia and diabetes,Diabetes37, 832–837.
22. Koh, et al. 2003. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR)- Activation
Prevents Diabetes in OLETF Rats. (Online)
(http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/content/full/52/9/2331?maxtoshow=&HITS
=&hits=&RESULTFORMAT=&fulltext=Diabetes+PPAR&andorexactfulltext=and
&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT, diakses 18 September
2010)
23. Bastaa, G., Ann Marie Schmidtb, and Raffaele De Caterina. 2004. Advanced
glycation end products and vascular inflammation: implications for accelerated
atherosclerosis in diabetes. Cardiovascular Research, 63: 582– 592
24. Kanthryn C.B., Tan, Wing-Sun Chow, Victor, H.G. AI, Christine Metz, Richard
Bucala, and Karen S.L. Lam. 2002. Advanced Glycation End Products and
Endothelial Dysfunction in Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 25:1055–1059, 2002
25. Aragno, M., E. Tamagno, V. Gato, E. Brignardello, S. Parola, O. Danni, G.
Boccuzzi. 2009. Dehydroepiandrosterone protects tissues of streptozotocin-treated
rats against oxidative stress. Free Radic. Biol. Med. 26(11/12), 1467–1474.
26. Sato, Y., Hotta, N., Sakamoto, N., Matsuoka, S., Ohishi, N., and Yagi, K. 2009.
Lipid peroxide level in the plasma of diabetic patients. Biochemical Medicineand
Metabolic Biology21(1),104-107.
27. Velazquez, E., Winocour, P.H., Kesteven, P., Alberti, K.G., and Laker, M.F. 2005.
Relation of lipid peroxides to macrovascular disease in type 2
diabetes.DiabeticMedicine8, 752-758.
28. Collier, A., Rumley, A., Rumley, A.G., Paterson, J.R., Leach, J.P., Lowe, G.D., and
Small, M. 2002. Free radical activity and hemostatic factors in NIDDM patients
with and without microalbuminuria.Diabetes41, 909-913.
29. MacRury, S.M., Gordon, D., Wilson, R., Bradley, H., Gemmell, C.G., Paterson,
J.R., Rumley, A.G., and MacCuish, A.C. 2003. A comparison of different methods
of assessing free radical activity in type 2 diabetes and peripheral vascular disease.
DiabeticMedicine10, 331-335.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
84
30. Neri, S., Bruno, C.M., Raciti, C., Dangelo, G., Damico, R., and Cristaldi, R. 2004.
Alteration of oxide reductive and haemostatic factors in type 2 diabetics. Journalof
Internal Medicine236, 495-500.
31. Griesmacher, A., Kindhauser, M., Andert, S.E., Schreiner, W., Toma, C., Knoebl,
P., Pietschmann, P., Prager, R., Schnack, C., and Schernthaner, G. 2005. Enhanced
serum levels of thiobarbituric-acid-reactive substancesin diabetes mellitus. Am. J.
Med. 98, 469-475.
32. Niskanen, L.K., Salonen, J.T., Nyyssonen, K., and Uusitupa, M.I. 2005. Plasma
lipid peroxidation and hyperglycaemia: a connection through
hyperinsulinaemia?Diabetic Medicine12, 802-808.
33. Santini, S.A., Marra, G., Giardina, B., Cotroneo, P., Mordente, A., Martorana, G.E.,
Manto, A., and Ghirlanda, G. 2007. Defective plasma antioxidant defenses and
enhanced susceptibility to lipid peroxidation in uncomplicated IDDM. Diabetes46,
1853-1858.
34. Cederberg, J., Basu, S., and Eriksson, U.J. 2001. Increased rate of lipid
peroxidation and protein carbonylation in experimental diabetic pregnancy.
Diabetologia44, 766-774.
35. Wautier, J. L., M. P. Wautier., A.M. Schmidt., G. M. Anderson., H. Rif, C.
Zoukourian., L. Capron., Chappey, S.D., Yan, J., Breyf, P.J., Guillausseauii, and
D. SterniI. 2004. Advanced glycation end products (AGEs) on the surface of
diabetic erythrocytes bind to the vessel wall via a specific receptor inducing oxidant
stress in the vasculature: A link between surface associated AGEs and diabetic
complications. Proc. Natl. Acad. Sci, Vol. 91, pp. 7742-7746.
36. Robertson, R.P. 2004. Chronic oxidative stress as a central mechanism for glucose
toxicity in pancreatic islet beta cells in diabetes, J. Biol. Chem. 279(41), 42351–
42354.
37. West, I.C., 2005. Radicals and oxidative stress in diabetes. Diabetic Med. 17, 171–
180.
38. Lenzen, S., J. 2006. Drinkgern, M. Tiedge, Low antioxidant enzyme gene expression
in pancreatic islets compared with various other mouse tissues, Free Radic. Biol.
Med., 20, 463–466.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
85
39. Lyons, T.J. 2001. Oxidized low density lipoproteins: a role in the pathogenesis of
atherosclerosis in diabetes?Diabet Med. 8, 411– 419.
40. Steiner, G. 2005. Atherosclerosis, the major complication of diabetes, Adv. Exp.
Med. Biol.189, 277–297.
41. Hiramatsu, K, S. Arimori, 2008. Increased superoxide production by mononuclear
cells of patients with hypertryglycerdemia and diabetes,Diabetes37, 832–837.
42. Wautier, J.L. and P.J. Guillausseau. 2001. Advanced Glycation End Products, Their
Receptors and Diabetic Angiopathy. Diabetes Metab, 27: 535-542
43. Mohamed, A.K., A. Bierhaus, S. Schiekofer, H. Tritschler, R. Ziegler, P.P.
Nawroth, 2009. The role of oxidative stress and NF-Kappa B activation in late
diabetic complications, Biofactors, 10, 157–167.
44. Nyunai, N., Njifutie, Njikam., Catherine, M and Philippe Pastoureau. 2006. Blood
Glucose Lowering Effect of Aqueous Leaf Extracts of Ageratum conyzoides in
Rats. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines,
Vol. 3, No. 3, pp. 76-79
45. Halliwel, B and Gutteridge, J. M. 2009. Free Radicals. In Biology and Medicine.
Third Edition. Oxford Science Publications.
46. Cerellio, A, N. Bortolotti, M. Pirisi, et al. 2007. Total plasma antioxidant capacity
predicts thrombosis-prone status in NIDDM patients,Diabetes Care. 20, 1589– 93.
47. Baldwin, A. S., Jr. 2006. The NF-kappa B and I kappa B proteins: new discoveries
and insights. Annu Rev Immunol 14:649-83.
48. Ghosh, G., G. van Duyne, S. Ghosh, and P. B. Sigler. 2005. Structure of NF-kappa
B p50 homodimer bound to a kappa B site. Nature 373:303-10.
49. Hayden, M. S., A. P. West, and S. Ghosh. 2006. NF-kappaB and the immune
response. Oncogene 25:6758-80.
50. Ghosh, G., G. van Duyne, S. Ghosh, and P. B. Sigler. 2005. Structure of NF-kappa
B p50 homodimer bound to a kappa B site. Nature 373:303-10.
51. Cramer, P., C. J. Larson, G. L. Verdine, and C. W. Muller. 2007. Structure of the
human NF-kappaB p52 homodimer-DNA complex at 2.1 A resolution. Embo J
16:7078-90.
52. Malek, S., Y. Chen, T. Huxford, and G. Ghosh. 2001. IkappaBbeta, but not
IkappaBalpha, functions as a classical cytoplasmic inhibitor of NF-kappaB dimers
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
86
by masking both NF-kappaB nuclear localization sequences in resting cells. J Biol
Chem276:45225-35.
53. Courtois, G., and T. D. Gilmore. 2006. Mutations in the NF-kappaB signaling
pathway: implications for human disease. Oncogene 25:6831-43.
54. Pahl, H. L. 2009. Activators and target genes of Rel/NF-kappaB transcription
factors. Oncogene 18:6853-66.
55. Weil, R., S. T. Whiteside, and A. Israel. 2007. Control of NF-kappa B activity by the
I kappa B beta inhibitor. Immunobiology 198:14-23.
56. Bonizzi, G., and M. Karin. 2004. The two NF-kappaB activation pathways and their
role in innate and adaptive immunity. Trends Immunol 25:280-8.
57. Dejardin, E. 2006. The alternative NF-[kappa]B pathway from biochemistry to
biology: Pitfalls and promises for future drug development. Biochemical
Pharmacology 72:1161-1179.
58. Hoffmann, A., G. Natoli, and G. Ghosh. 2006. Transcriptional regulation via the
NFkappaB signaling module. Oncogene 25:6706-16.
59. Boulanger CM, Vanhoute PM. The endothelium: a pivotal role in health and
cardiovascular disease. Servier International. France, 2004
60. Beckman JA, Creager MA, Libby P. Diabetes and atherosclerosis: epidemiology,
pathophysiology, and management. JAMA, 287:2570-81, 2002
61. Creager MA, Luscher TF, Consentino F, Beckman JA. Diabetes and vascular
disease. Pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: Part I.
Circulation. 108:1527-32, 2003
62. Mc Veigh GE, Brennan GM, Johnston GD, et al. Impaired endothelium dependent
and independent vasodelation in patient with type-2 diabetes mellitus. Diabetologia.
35:771-76, 2002
63. Beckman JA, Goldfine AB, Gordon MB, et al. Ascorbate restores endothelium
dependent vasodilation impaired by acute hyperglycemia in humans. Circulation.
103:1618-23, 2001
64. Hink U, Li H, Mollnau H, et al. Mechanisms underlying endothelial dysfunction in
diabetes mellitus. Circ Res. 88:E14-E22.,2001
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
87
65. Hempel A, Maasch C, Heintze U, Lindschau C, Dietz R, Luft FC, Haller H. High
glucose concentration increase endothelial cell permeability via activation of protein
kinase-C alpha. Circulation Res. 81:363-71, 2007
66. Esper, R., Vilariño, J., Machado, R., and Paragano A. 2008.Endothelial Dysfunction
in Normal and Abnormal Glucose Metabolism. Adv Cardiol. Basel, Karger, vol. 45,
pp 17-43
67. Sofia, D. 2003. Antioksidan dan Radikal Bebas. (Online) (http://www.chem-is-
try.org/?sect=artikel&ext=81, diakses 23 September 2010)
68. Culliton BJ. Neuroimmunie basis of acupuncture. Nat Med 3: 1307, 2007.
69. Lock MM. East Asian Medicine in Urban Japan: Varieties of Medical Experience
(ComparativeStudies of Health Systems & Medical Care).Los Angeles: University
of California Press , 2001.
70. Cho ZH, Chung SC, Jones JP, Park JB, Park HJ, Lee HJ, Wong EK, Min BI. New
findings of the correlation between acupoints and corresponding brain cortices using
functional MRI. Proc NatlAcad Sci USA 95: 2670-2673, 2008.
71. Murase K, Kawakita K. Diffuse noxious inhibitory controls in anti-nociception
produced byacupuncture and moxibustion on trigeminal caudalis neurons in rats.
Jpn J Physiol 50: 133-140,2001.
72. Uchida S, Kagitani F, Suzuki A, Aikawa Y. Effect of acupuncture-like stimulation
on corticalcerebral blood flow in anesthetized rats. Jpn J Physiol 50: 495-507,
2000.Acupuncture. NIH Consensus Statement 15: 1-34, 2007.
73. Chung SH, Dickenson A. Pain, enkephalin and acupuncture. Nature 283: 243-244,
2005.
74. Niimi H, Yuwono HS. Asian traditional medicine: from molecular biology to organ
circulation. Clin Hemorheol Microcirc 23: 123-125, 2005.
75. Gongwang L, Hyodo A. Fundamentals of Acpuncture and Moxibustion. Tianjin,
China: Tianjin Science and Technology Translation and Publishing Corp., 2004.
76. Billingham, M.E., J. Morley, J.M. Hanson, R.A. Shipolini and C.A. Vernon. Letter;
an anti-inflammatory peptide from bee venom. Nature 245: 163–164, 2006.
77. Kwon, Y.B., J.D. Lee, H.J. Lee, H.J. Han, W.C. Mar, S.K. Kang, A.J. Beitz and J.H.
Lee. Bee venom injection into an acupuncture point reduces arthritis associated
edema and nociceptive responses. Pain 90: 271–280, 2007.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
88
78. Kang, S.S., C.C. Pak and S.H. Choi. The effect of Shole bee venom on arthritis. Am.
J. Chin. Med.30(1): 73–80, 2002.
79. Lariviere WR, Melzack R. 2006. The bee venom test: a new tonic-pain test. Pain
66:271–277.
80. Lariviere WR, Wilson SG, Laughlin TM, Kokayeff A, West EE, Adhikari SM, Wan
Y, Mogil JS. 2002. Heritability of nociception. III. Genetic relationships among
commonly used assays of nociception and hypersensitivity. Pain 97:75–86.
81. Chen HS, Chen J. 2004. Secondary heat, but not mechanical, hyperalgesia induced
by subcutaneous injection of bee venom in the conscious rat: effect of systemic MK-
801, a non-competitive NMDA receptor antagonist. Eur J Pain 4:389–401.
82. Chen J. 2003. The bee venom test: a novel useful animal model for study of spinal
coding and processing of pathological pain information. In: Experimental
pathological pain: from molecules to brain functions (Chen J, Chen CAN, Han JS,
Willis WD, eds), pp 77–110. Beijing: Science Press.
83. Lee JH, Kwon YB, Han HJ, Mar WC, Lee HJ, Yang IS, Beitz AJ, Kang SK. 2001.
Bee venom pretreatment has both an antinociceptive and anti-inflammatory effect
on carrageenan-induced inflammation.J Vet Med Sci 63:251–259.
84. Tu AT. 2007. Venoms: Chemistry and molecular biology. Toronto: John Wiley.
85. Maeda M, Kachi H, Ichihashi N, Oyama Z, Kitajima Y. The effect of electrical
acupuncture-stimulation therapy using thermoguraphy and plasma endothelin (ET-
1) levels in patients with progressive systemic sclerosis (PSS). J Dermatol Sci
2008;17:151–5
86. Litscher G, Schwarz G, Sandner-Kiesling A, Hadolt I. Robotic transcranial Doppler
sonography probes and acupuncture. Intern J Neuroscience 2008;95:1–15
87. Lie P, Pitsillides KF, Rendig SV, Pan H-L, Longhurst JC. Reversal of reflex-
induced myocardial ischemia by median nerve stimulation: a feline model of
electroacupuncture. Circulation 2008;97:1186–94
88. Boutouyrie P, Corvisier R, Azizi M, Lemoine D, Laloux B, Hallouin M-H, Laurent
S. Effects of acupuncture on radial artery hemodynamics: controlled trials in
sensitized and naïve subjects. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2001;280:H628–
H633
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
89
89. Hsieh J-C, Tu C-H, Chen F-P, Chen MC, Yeh TC, Cheng H-C, Wu Y-T, Liu R-S,
Ho L-T. Activation of the hypothalamus characterizes the acupuncture stimulation
at the analgesic point in human: a positron emission tomography study. Neurosci
Lett 2001;107:105–8
90. Uchida S, Kagitani F, Suzuki A, Aikawa Y. Effect of acupuncture-like stimulation
on cortical cerebral blood flow in anesthetized rats. Jpn J Physiol 2005;50:495–507
91. Loaiza LA, Yamaguchi S, Ito M, Ohshima N. Electroacupuncture stimulation to
muscle afferents in anesthetized rats modulates the blood flow to the knee joint
through autonomic reflexes and nitric oxide. Auton Neurosci 2002;97:103–9
92. Makiko Komori, Katsumi Takada. Microcirculatory Responses to Acupuncture
Stimulation and Phototherapy.Anesth Analg 2009;104:308–11
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
91
BENALU TEH (SCRURRULA ATROPURPUREA) SEBAGAI HERBAL
ALTERNATIF ANTIBAKTERI UNTUK PENGOBATAN INFEKSI
METHICHILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)
Novra Arya Sandi, Siti Isrina Oktavia Salasia
Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
Parasite tea (Scurrula atropurpurea) is a plant commonly used as traditional medicine.
It contains active substancessuch as flavonoids that are potential for
antibacterial. Recently,bacterial resistance to various antibiotics has beenincreased. It
takes an effort to find a medicinal plant with a potential as a proper and safe
antibiotic. The study explored the alternativeantibiotic from parasite tea for the
treatment of mastitis due to Staphylococcus aureus that is resistance to several
antibiotics. The study was aimed to the antibacterial activity of parasite tea compounds
against S. aureusantibiotics multiresistant. Based on sensitivity test of various
antibiotics previously, it was known that the majority of S. aureus was resistant to
oxacilin (87.5%), erythromycin (71.97%) and some isolates were also resistant to
tetracycline (37.46%), ampicillin (25%) and gentamicin (21.87%). The results of
previous studies also showed that S. aureuswere resistance to tetracycline, gentamicin,
erythromycin, oxacilin, ampicilin and penicillin G. Staphylococcus aureus also has a
meditative (intermediate) character of the carious antibiotics which tend toward
resistance to tetracycline, gentamicin, erythromycin, ampicillin and penicillin G. An
alternativeto solve the resistance of S. aureus to several antibiotics wasto utilize active
substance contained in parasit tea to kill the bacteria. The active compounds contained
in parasit tea plantssuch as tannins, phenols, saponins, alcaloids, flavonoids and
triterpene steroide have potential antibacterial activity, especially against S.aureus. The
potential antibacterial activities of the active substances varies depending on the
solvent,extraction and concentration of plant extracts.
Keywords: Parasit tea, mastitis, Stapylococcus aureus, herbal medicine, alternative
antibiotic
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
92
PENDAHULUAN
Mastitis merupakan radang ambingyang disebabkan oleh infeksi Staphylococcus
aureus (S. aureus), dapat terjadi secara klinis, namun seringkali terjadi secara subklinis
dan kronis (Bannerman dan Wall, 2005). Mastitis sering terjadi pada sapi perah dan
menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi peternakan sapi perah di
seluruh dunia (Quinn et al., 2002). Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh mastitis,
terutama mastitis subklinis, meliputi penurunan produksi dan mutu susu, peningkatan
biaya perawatan dan pengobatan, pengafkiran ternak lebih awal serta pembelian sapi
perah baru (Subronto, 2003). Staphylococcus aureusdapat menginfeksi manusia atau
bersifat zoonosis (Warsa,1994; Bannerman dan Wall, 2005) dan dapat menyebabkan
keracunan makanan karena mampu menghasilkan dua jenis toksin yang mempunyai
akifitas sebagai superantigen yaitu enterotoksin dan Toxic Shock Syndrom (TSS)
toxin(Anonim, 1997; Clements, 1997) .
Menurut Gur et al. (2006),bakteri mempunyai potensi resistensi tehadap
berbagai macam antibiotik akibat pemberian antibiotika secara sembarangan dan tidak
mengikuti aturan. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam pengobatan penyakit-
penyakit infeksius. Resistensi bakteri terhadap antibiotik telah menjadi perhatian dunia
secara global (Westh et al.,2004). Sejak resistensi bakteri terhadap antibiotik meningkat,
mulai muncul perhatian untuk menemukan obat alami sebagai antimikrobial. Usaha
untuk menemukan antimikrobial alternatif sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk
mengobati penyakit infeksi bakteri termasuk mastitis pada sapi perah.
Salah satu penyebab resistensi bakteri adalah penghentian antibiotik sebelum
penyakit sembuh, dan pemberian obat di bawah dosis standar. Berdasarkan uji
sensitivitas terhadap berbagai antibiotik, diketahui bahwa sebagian besar S. aureus telah
resisten terhadap oksasilin (87,5%), eritromisin (71,97%) dan ada beberapa isolat yang
juga resisten terhadap tetrasiklin (37,46%), ampisillin (25%) dan gentamisin
(21,87%)(Salasia,2005). Berdasar penelitian yang dilakukan Waranurastuti (2009),
Staphylococcus aureustelah resisten terhadap tetrasiklin, gentamisin, eritromisin,
oksasilin, ampisilin dan penisilin G.Selain itu,Staphylococcus aureus juga memiliki
sifat intermedier terhadap berbagai antibiotika yang cenderung ke arah resisten terhadap
tetrasiklin, gentamisin, eritromisin, ampisilin dan penisilin G.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
93
Infeksi yang disebabkan bakteri yang resisten terhadap berbagai antibiotik
memerlukan penanganan dengan obat baru yang memiliki potensi tinggi terhadap
infeksi.Pengkajian zat yang berkhasiat sebagai antibakteri perlu dilakukan untuk
menemukan produk antimikroba yang berpotensi untuk menghambat atau membunuh
bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh
adalah memanfaatkan zat aktif pembunuh bakteri yang terkandung dalam tanaman obat.
Penggunaan obat tradisional telah lama berkembang di Indonesia sebagai salah satu
alternatif untuk menunjang program kesehatan masyarakat (Hembing, 1996).
Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antibiotika herbal adalah
benalu teh Scurrula atropurpureadengan potensi sebagai antibakteri,antiviral,
antiinflamasi, antialergi, antimutagenik, antitrombotik, dan aktivitas vasodilatasikarena
mengandung flavonoid (Larbier dan Leclerco 1992; Miller, 1996). Sampai saat ini
belum banyak penelitian mengenai senyawa aktif dalam benalu teh, di antaranya
senyawa yang berkhasiat sebagai antitoksin dan antioksidan. Gusvianiet al.,(2002)
melaporkan bahwa benalu teh mengandung kuersitrin yang salah satu aktivitasnya
adalah meningkatkan aktivitas fagositosis, meningkatkan jumlah lekosit total,
mempunyai kemampuan menstimulasi respon imun spesifik, seluler dan respon imun
humoral.
METODE
Penyusunan karya tulis ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan
kualitatif melalui studi literatur terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
Tanaman Benalu teh
Benalu teh merupakan tanaman parasit obligat dengan batang menggantung,
berkayu, silindris, berbintik-bintik, coklat,memiliki daun tunggal, berhadapan,
berbentuk lonjong, ujung agak meruncing, pangkal membulat, tepi rata, panjang 5-9 cm,
lebar 2-4 cm, dengan permukaan atas daun berwarna hijau sedangkan permukaan bawah
berwarna coklat. Bunga Benalu teh tergolong bunga majemuk, berbentuk payung,
terdiri dari 4-6 bunga, terdapat diketiak daun atau di ruas batang, tangkai pendek,
kelopak berbentuk kerucut terbalik dengan panjang ± 3 mm, bergigi empat, panjang
benang sari 2-3mm,kepala putik berbentuk tombol, dengan panjang tabung mahkota 1-2
cm, taju mahkota melengkung ke dalam dan berwarna merah. Buah Benalu teh
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
94
berbentuk kerucut terbalik, dengan panjang ± 8 mm, berwarna coklat. Akar Benalu teh
menempel pada pohon inang, berwarna kuning kecoklatan dan berfungsi sebagai
penghisap (Departemen Kesehatan RI, 1997).
Sistematika Benalu teh menurut sumber Departemen Kesehatan RI (1997),
adalah sebagai berikut:
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Santalales
Suku : Loranthaceae
Marga : Scurrula
Jenis :Scurrula artopurpurea (BI). Dans.
Daun dan batang Benalu teh mengandung saponin dan tanin. Daun Benalu teh
juga mengandung alkaloid dan flavonoid (Departemen Kesehatan RI, 1997). Sementara
itu, menurut Winarno et al.(2000) daun dan batang tanaman ini mengandung senyawa
alkaloid, flavonoid, glikosida,triterpen,saponin, dan tanin.
Flavonoid yang terkandung di dalam Benalu teh berguna sebagai antioksidan
dan kemampuannya mengurangi aktivitas radikal hidroksi, anion superoksida, dan
radikal peroksida lemak yang menjadikan flavonoid berperan penting serta sangat erat
kaitannya dengan proses dan epidemiologi penyakit (Larbier dan Leclerco 1992;
Miller,1996). Selain itu, potensi lain dari flavonoid adalah sebagai antibakteri,antiviral,
antiinflamasi, antialergi, antimutagenik, antitrombotik, dan aktivitas vasodilatasi
(Larbier dan Leclerco 1992; Miller, 1996).
Ekstrak benalu teh spesies Scurrula atropurpurea mengandung 16 bahan
bioaktif yang terdiri atas dari enam senyawa asam lemak, dua santin, dua
glikosidaflavonol, satu glikosidamonoterpen, satu glikosida lignan, dan empat flavon
(Ohashi et al.,2003). Berdasarkan dugaan bahwa asam glukuronat terdapat dalam the,
maka kemungkinan juga terdapat dalam benalu teh karena adanya penyerapan unsur
hara dari tanaman inangnya sehingga memiliki kemiripan kandungan senyawa kimia.
Benalu teh mengandung glikosida (Chairul et al.,1998) yang merupakan asam organik
hasil metabolit sekunder yang dapat mengikat racun dan membuatnya tidak beracun
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
95
(detoksin). Berdasarkan penelitian dari hasil analisis kadar senyawa katehin dari
beberapa benalu the, adanya kadar katehin yang tinggi dapat mendukung keefektifan
suatu tanaman untuk digunakan sebagai obat karena memiliki manfaat yang sangat
banyak (Tambunan et al., 2003; Simanjuntak et al., 2004).
Senyawa aktif yang terdapat didalam tanaman benalu teh seperti tannin, fenol,
saponin, alkaloid, flavanoid dan steroida triterpen memiliki potensi sebagai antibakteri
terutama terhadap 3 bakteri patoghen E. coli, S. aureus dan C. albicans. Potensi yang
dimilki oleh zat-zat aktif tersebut bervariasi tergantung pada solven dan ekstraksi serta
konsentrasi dari ekstrak tanaman (Okigbo et al., 2009; Eyob et al., 2008; Jagtap et al.,
2009; Elazavazhagan dan Arucanalam, 2010).
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus adalah mikroorganisme berbentuk coccus (bulat)yang
biasanya tersusun berkelompok seperti buah anggur, berpasangan dan rantai pendek
(Merchant dan Parker, 1961). Staphylococcus aureus memiliki sifat tidak membentuk
spora, tidak bergerak, gram positif, fakultatif anaerob, memfermentasi karbohidrat,
mencairkan gelatin, katalase positif (Merchant dan Parker, 1961;Todar, 2005). Bakteri
ini mudah tumbuh pada berbagai media perbenihan, menghasilkan pigmen yang
bervariasi dari putih sampai kuning tua.Staphylococcus aureus patogen dapat melisiskan
darah dan mengkoagulasi plasma (Jawezt et al., 1986).
Staphylococcus terdistribusi luas di seluruh dunia dan merupakan flora normal
pada kulit dan membran mukosa manusia dan hewan (Merchant dan Parker,1961). S.
aureus berbentuk bulat dan biasanya begerombol tidak beraturan, uji katalase positif,
memfermentasi glukosa dalam keadaaan anaerobik fakultatif dan membentuk asam
manitol secara anaerobik (Foster,2004; Tarverna et al., 2007). Ukuran diameter bakteri
tersebut 0,7-12 μm, pada kultur muda 1 μm (Jawetz et al,. 2001;Sherris, 1984).
Staphylococccus aureus dapat tumbuh pada kondisi aerob atau anaerob fakultatif
dengan suhu optimumnya 37°C, namun pembentukan pigmen yang terbaik adalah pada
temperatur kamar (20-35°C). Batas suhu untuk pertumbuhannya adalah 15°C dan 40°C
dengan pH optimum 7,4(Warsa, 1994).
Staphylococcus aureus mengandung polisakarida dan protein yang bersifat
antigenik dan merupakan substansi yang penting dalam struktur dinding sel.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
96
Staphylococcus aureus memiliki kapsul yang diselubungi oleh polisakarida dan
merupakan lapisan terluar dari dinding sel Staphylococcus(Tarverna et al., 2007).
Kapsul polisakarida merupakan salah satu komponen permukaan yang berperan dalam
patogenesitas mastitis. Kapsul S.aureus berfungsi mencegah fagosit dari interaksi
dengan determinan subkapsular bakteri, sehingga tidak terjadi penelanan oleh
fagosit(Roth, 1988). Kapsul polisakarida sebagai antifagositosis beperan melindungi
bakteri selama terjadinya proses infeksi. Bakteri yang memiliki kapsul lebih virulen
dibanding bakteri yang tidak memilki kapsul (Buzzola et al., 2007).
Dinding sel S. aureus tersusun atas 3 komponen utama yaitu peptidoglikan,
asam teikoat dan protein A. Berbagai komponen S. aureus yang berperan dalam
mekanisme infeksi atau sebagai determinan virulen adalah polisakarida dan protein
yang merupakan substansi penting dalam dinding sel, seperti protein adesin
hemaglutinin dan glicoprotein fibronectin (Nelson et al., 1991). Protein permukaan ini
berperan dalam proses kolonisasi bakteri di dalam jaringan inang. Invasin berperan
dalam penyebaran bakteri di dalalm jaringan, midalnya leukocidin, kinase,
hyaluronidase, kapsul dan protein A yang dapat menghambat fagositosis oleh leukosit
polimorfonuklear. Substansi biokimia, seperti karotenoid dan produk katalase, dapat
membuat bakteri bertahan hidup dalam fagosit. Protein A, koagulase dan clumping
factor berperan untuk menghindarkan diri dari respon imun inang(Haraldsson dan
Jonsson, 1984).Produksi enzim koagulase merupakan faktor patogenitas utama dari S.
aureus yang membedakan S. aureus dari Staphylococcus lainnya (Levinson danJawetz,
2003; Bello danQahtani, 2005).
Selama beberapa tahun terakhir dilaporkan terjadi peningkatan infeksi
Staphylococcus koagulase negatif sebagai penyebab mastitis di seluruh dunia yang
dapat menyebabkan penurunan produksi susu sebesar 8,7% dalam satu masa laktasi.
Dalam suatu peternakan pernah dilaporkan dapat diisolasi Staphlococcus koagulase
negatif sebesar 67,4% yang seringkali dapat diisolasi bersamaan dengan bakteri
penyebab environmental mastitis(Oliver, 2000).
Penanganan Infeksi Bakteri
Penanganan terhadap infeksi yang ditimbulkan oleh S. aureus saat ini umumnya
menggunakan terapi antibiotik dengan jenis dan spektrum yang berbeda-beda. Secara
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
97
umum menurut Mills et al. (1987) berdasarkan ditemukannya kuman penyebab infeksi
atau tidak, maka terapi antibiotika dapat dibagi menjadi dua, yaitu terapi secara empiris
dan terapi definitif.Terapi secara empiris, pada banyak keadaan infeksi, kuman
penyebab infeksi belum dapat diketahui atau dipastikan pada saat terapi antibiotika
dimulai. Pemilihan jenis antibiotika diberikan berdasarkan perkiraan kemungkinan
kuman penyebabnya, berdasarkan pada pengalaman yang layak atau pada pola
epidemiologi kuman setempat. Pertimbangan utama dari terapi empiris adalah
pengobatan infeksi sedini mungkin akan memperkecil resiko komplikasi atau
perkembangan lebih lanjut dari infeksinya, misalnya dalam menghadapi kasus-kasus
infeksi berat, infeksi pada pasien dengan kondisi depresi imunologik. Kekurangan dari
terapi empirik antara lain meliputi perkiraan seandainya pasien tidak menderita infeksi
atau kepastian kuman penyebab tidak dapat diperoleh kemudian karena sebab-sebab
tertentu, maka terapi antibiotika seolah-olah dilakukan secara sembarangan. Karena itu,
dari metode terapi ini akan timbul berbagai macam kerugian seperti resistensi bakteri
serta tidak tercapainya manfaat klinik yang diinginkan. Terapi secara definitifdilakukan
berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologis yang sudah pasti, jenis kuman maupun
spektrum kepekaannya terhadap antibiotika. Dalam praktik sehari-hari,terapi antibiotika
umumnya dilakukan secara empiris. Setelah hasil pemeriksaan mikrobiologis
menunjukkan ketidakcocokan dalam pemilihan antibiotika, maka antibiotika dapat
diganti kemudian dengan jenis yang sesuai. Metode terapi ini lebih akurat dan dapat
mengatasi penyakit infeksi serta tercapainya manfaat klinik yang diinginkan.
Pemilihan antibiotika juga sangat berpengaruh dalam terapi penyakit infeksi
akibat bakteri, khususnya S. aureus penyebab utama mastitis pada sapi perah. Dalam
menentukan pilihan terhadap antibiotik yang akan digunakan harus menggunakan
prinsip-prinsip tertentu yang dapat mengurangi dan mengatasi penyakit infeksi tersebut.
Grahame-Smith dan Aronson (1985) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip proses
keputusan pemilihan dan pemakaian antibiotika secara ringkas mencakup langkah-
langkah berikut:
1. Melakukan diagnosis terhadap infeksi. Hal ini bisa dikerjakan secara klinis ataupun
pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lain yang diperlukan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
98
2. Menentukan Kemungkinan kuman penyebab infeksi, dipertimbangkan dengan
perkiraan ilmiah berdasarkan pengalaman setempat yang layak dipercaya atau
epidemiologi setempat atau dari informasi-informasi ilmiah lain.
3. Menentukan apakah pemberian antibiotika benar-benar diperlukan karena pada
sebagian infeksi tidak memerlukan terapi antibiotika seperti infeksi virus saluran
pernafasan atas, keracunan makanan karena kontaminasi kuman-kuman enterik.
4. Apabila diperlukan antibiotika, maka pemilihan antibiotika yang sesuai harus
berdasarkan kondisi hewan ternak (pasien), spektrum antikuman, pola
sensitifitas,sifat farmakokinetika,ada tidaknya kontra indikasi pada pasien,ada
tidaknya interaksi yang merugikan,bukti akan adanya manfaat klinik dari masing-
masing antibiotika untuk infeksi yang bersangkutan berdasarkan informasi ilmiah
yang terpercaya.
5. Menentukan dosis, cara pemberian,serta lama pemberian berdasarkan sifat-sifat
kinetika masing-masing antibiotika dan fungsi fisiologis sistem tubuh seperti fungsi
ginjal, fungsi hepar dan fungsi sistem tubuh lainnya.
6 Mengevaluasi efek obat seperti manfaat obat, menentukan kapan harus diganti
dengan obat lain atau dihentikan serta adakah efek samping yang terjadi akibat
pemberian obat tersebut.
Dampak negatif pemakaian antibiotika secara irasional menurut Grahame-Smith
dan Aronson (1985), mencakup terjadinya resistensi kuman, timbulnya strain-strain
kuman yang resisten, terjadinya peningkatan efek samping dan toksisitas antibiotika,
yang terjadi secara langsung karena pengaruh antibiotika yang bersangkutan atau karena
terjadinya superinfeksi, terjadinya pemborosan biaya karena pemakaian antibiotika yang
berlebihan pada kasus-kasus yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik, dan tidak
tercapainya manfaat klinik optimal dalam pencegahan maupun pengobatan penyakit
infeksi.
Apabila tetap terjadi resistensi bakteri terhadap antibiotik yang diberikan dengan
metode terapi yang benar, maka salah satu cara untuk menanggulangi hal ini adalah
dengan menemukan alternatif antibiotik dari tanaman obat yang memiliki potensi
sebagai antibakteri. Penggunaan antibiotik dari tumbuhan juga diharapkan memiliki
nilai ekonomis dari segi mudah dan murah untuk serta memiliki residu yang tidak
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
99
berbahaya bagi produk sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam pengendalian
bidang hewan produksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh Salasia et al. (2005) pada sapi perah
di daerah Yogyakarta, Boyolali dan Baturaden (Jawa tengah) diketahui bahwa S.aureus
telah resisten terhadap beberapa antibiotik yang dirangkum dalam Tabel 1. Berdasarkan
tabel tersebut, uji sensitifitas terhadap berbagai antibiotik diketahui bahwa sebagian
besar S. aureus telah resisten terhadap oksasilin (87,5%), eritromisin (71,97%) dan ada
beberapa isolat yang juga resisten terhadap tetrasiklin (37,46%), ampisillin (25%) dan
gentamisin (21,87%).
Tabel 1. Persentase resistensi 32 isolat S.aureus isolat sapi perah terhadap berbagai
antibiotika
Sumber: Salasia et al. (2005)
Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh Padli (2010) terhadap
aktifitas antibakteri terhadap S. aureus dari benalu teh dengan konsentrasi ekstrak
metanol benalu teh (Scrulla atropurpurea) 2%, 1% , 0,5%, 0,25%, dan 0,125%,
menunjukkan bahwa ekstrak metanol dan senyawa aktif benalu teh mempunyai aktivitas
antibakteri terhadap S. aureus dengan KBM (kadar bunuh minimal) 1%.
Mastitis merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kerugian besar dalam
bidang pangan dan kesehatan serta perekonomian. Kejadian mastitis pada sapi perah di
Indonesia sangat tinggi (95-98%) dan menimbulkan banyak kerugian
(Sudarwanto,1999). Staphylococcus aureus yang dapat diisolasi dari berbagai pangan
olahan asal hewan kemungkinan karena adanya pencemaran yang berasal dari
lingkungan baik yang berasal dari hewan, manusia maupun alat-alat yang digunakan
No Jenis Antibiotika Sensitif Intermediet Resisten
1 Ampisilin 24 (75%) 0 (0%) 8 (25%)
2 Eritromisin 4 (12,50%) 5 (15,57%) 23 (71,97%)
3 Gentamisin 0 (0 %) 25 (78,13%) 7 (21,87%)
4 Oksasilin 4 (12,5%) 0 (0%) 28 (87,5%)
5 Tetrasiklin 1 (3,16%) 19 (59,38%) 12 (37,46%)
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
100
dalam proses pembuatan makanan. Kondisi penyimpanan makanan yang tidak sesuai
kemungkinan besar menyebabkan terjadinya pertumbuhan S. aureus. Penyakit-penyakit
akibat keracunan pangan (food-borne diseases) merupakan masalah utama yang
berdampak pada kesehatan masyarakat. Di Amerika setiap tahun hampir 6-80 juta orang
terkena keracunan pangan dan menyebabkan kematiansekitar 9.000 orang dengan biaya
penanganankasus tersebut sekitar 5 Miliar dolar (Balabandan Rasooly, 2000; LeLoir et
al.,2003). Penyebabkeracunan yang paling sering adalah akibatenterotoksin yang
dihasilkan oleh S.aureus.
Selama beberapa tahun terakhir dilaporkan terjadinya peningkatan infeksi oleh
Staphylococcus koagulase negatif sebagai penyebab mastitis di seluruh dunia yang
dapat menyebabkan penurunan produksi susu sebesar 8,7% dalam satu masa laktasi.
Oliver (2000) juga mengemukakan bahwa dalam suatu peternakan dapat diisolasi
Staphlococcus koagulase negatif sebesar 67,4% yang seringkali dapat diisolasi
bersamaan dengan bakteri penyebab environmental mastitis.
Penanggulangan infeksi oleh mikroorganisme memerlukan obat-obat yang
mempunyai daya kerja optimal dan efek samping kecil. Dewasa ini, penggunaan
antibiotik sangat banyak terutama dalam pengobatan yang berhubungan dengan infeksi.
Kenyataan menunjukkan bahwa masalah penyakit infeksi terus berlanjut. Hal tersebut
terjadi akibat resistensi bakteri terhadap antibiotik, sehingga diperlukan usaha
pengembangan obat tradisional untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
Selama ini penanganan mastitis dilakukan dengan pemakaian antibiotika.
Pemakaian antibiotika yang tidak tepat dapat meninggalkan residu di dalam susu,
menimbulkan alergi, resistensi bakteri serta mempengaruhi proses pengolahan hasil
susu. Untuk menghindari masalah tersebut dibutuhkan strategi baru dalam penanganan
mastitis. Berdasar kajian penelitian S. aureus penyebab mastitis telah resiten terhadap
berbagai antibiotik seperti tetrasiklin, gentamisin, eritromisin, oksasiklin, ampisilin dan
penisilin G (Waranustuti, 2009). Penelitian oleh Salasia et al. (2005) uji sensitifitas
terhadap berbagai antibiotik diketahui bahwa sebagian besar S. aureus telah resisten
terhadap oksasiklin (87,5%), eritromisin (71,97%) dan ada beberapa isolat yang juga
resisten terhadap tetrasiklin (37,46%), ampisillin (25%) dan gentamisin
(21,87%).Berdasar data tersebut, dibutuhkan alternatif pengobatan mastitis yang efektif
untuk mengatasi bakteri yang resisten dengan residu yang tidak tertinggal pada produk
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
101
susu. Secara umum obat yang berasal dari tumbuhan memiliki residu yang lebih sedikit
dibanding antibiotik yang tidak berasal dari tanaman serta cenderung membutuhkan
biaya yang lebih murah.
Pada kasus mastitis dibutuhkan penanganan yang serius karena berdampak pada
kesehatan manusia.Salah satu penanganan yang dibutuhkan adalah pengobatan sapi
perah dengan menggunakan obat yang aman bagi ternak tersebut serta tidak
meninggalkan residu yang berbahaya pada susu. Salah satu alternatif yang dapat
ditempuh adalah memanfaatkan zat aktif pembunuh bakteri yang terkandung dalam
tanaman obat. Penggunaan obat tradisional merupakan salah satu alternatif dan telah
lama berkembang di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Pengobatan dengan
pemberdayaan obat tradisional merupakan salah satu komponen program pelayanan
kesehatan dasar yang digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan penduduk (Hembing, 1996).
Manfaat dari penggunaaan antibiotik alternatif dapat diharapkan mengurangi
risiko residu yang tertinggal pada susu serta menekan biaya pembelian antibiotik yang
terlalu mahal. Selain itu, manfaat lain dari penggunaan komponen materi antibakteri
yang berasal dari tanaman obat antara lain lebih sedikit efek samping, toleransi pasien
lebih baik, tidak terlalu mahal, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang
serta dapat diperbaharui di alam (Gur et al.,2006).
Berbagai macam penelitian telah dillakukan untuk mengidentifikasi komponen
di dalam tanaman obat yang berguna sebagai antibiotik yang efektif.Pengobatan
tradisional di seluruh dunia yang menggunakan herbal dapat digunakan sebagai sumber
informasi penting untuk menemukan alternatif antibiotik (Samy dan
Gopalakhrisnakone, 2008). Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibiotik
adalah benalu teh. Benalu teh (Scrulla atropurpurea) dengan konsentrasi 1%
mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus (Padli, 2010). Daya bunuh benalu
teh terhadap S. aureus tersebut kemungkinan karena mengandung zat aktif tannin, fenol,
saponin, alkaloid, flavanoid dan steroida triterpen. Senyawa aktif tersebut yang terdapat
di dalam benalu teh memiliki potensi sebagai antibakteri terutama terhadap 3 bakteri
patogen E. coli, S. aureus dan C. Albicans (Okigbo et al., 2009).
Selain itu, menurut hasil penelitian Gusvianiet al.(2002), benalu teh
mengandung kuersitrin yang salah satu aktivitasnya adalah meningkatkan aktivitas
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
102
fagositosis, meningkatkan jumlah leukosit total, menstimulasi respon imun seluler
maupun humoral. Potensi yang ada pada benalu teh kemungkinan dapat meningkatkan
imunitas hewan terhadap infeksi S. aureus.
Potensi yang dimilki oleh zat-zat aktif benalu teh bervariasi tergantung pada
solven dan ekstraksi serta konsentrasi dari ekstrak tanaman (Okigbo et al., 2009; Eyob
et al., 2008; Jagtap et al., 2009; Elazavazhagan dan Arucanalam, 2010). Oleh karena
pemanfaatan potensi benalu tehsebagai antibakterial perlu dikembangkan melalui
penelitian lebih lanjut, melalui pembuktian secara in vivo dengan menggunakan hewan
percobaan. Hasil penelitian lanjut diperlukan untuk memperoleh bukti secara biologis
bahwa benalu teh dapat digunakan untuk mengatasi infeksi S. aureus yang diketahui
bersifat multiresisten terhadap berbagai antibiotika, untuk dapat diterapkan pada dunia
peternakan skala kecil maupun industri.
KESIMPULAN
Benalu teh merupakan tanaman yang memiliki potensi sebagai antibiotik
alternatif untuk pengobatan infeksi bakteri S. aureus karena mengandung beberapa zat
aktif seperti, fenol, saponin, alkaloid, flavanoid dan steroida triterpen. Potensi yang
dimilki oleh zat-zat aktif tersebut bervariasi tergantung pada solven dan ekstraksi serta
konsentrasi dari ekstrak tanaman sehingga dapat memberikan efek yang efektif.
Penggunaan antibiotik alternatif dari tumbuhan benalu teh diharapkan dapat membantu
mengatasi penyakit mastitis yang disebabkan S. aureus multiresisten antibiotik secara
tepat dan aman bagi kesehatan manusia dan hewan. Potensi benalu teh sebagai
antibiotika herbal perlu dikaji lebih lanjut melalui percobaan secara in vivo untuk dapat
diterapkan pada dunia peternakan skala kecil maupun industri.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim,1997. Bacterial Toxins: Staphylococcal Enterotoxins; Toxic Shock Syndrome
Toxin and StreptococccalPyrogenicExotoxins.
http://www.urmc.rochester.edu/SMD/mbi.bactox/sthent.htm
Balaban, N. and Rasooly, A., 2000. Review staphylococcal enterotoxins. J.
FoodMicrobiol.61, 1-10.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
103
Bannerman, D. D. and Wall, R. J,. 2005. A Novel Strategy for the Prevention of
Staphylococcus aureus-Induced Mastitis in Dairy Cows. Information Systems
for Biotechnology News Report. Virginia Tech University. USA. 1 - 4.
Bello, C. S. and Qahtani, A., 2005. Pitfalls in the Routine Diagnosis of Staphylococcus
aureus. African J. Biotech. 4 (1): 83 - 86.
BuzzolaF. R., Alvarez, L. P., Tuchscherr, L. P. N., Barbagelata, M. S., Latta S. M.,
Clvinho, L., Sordelli D. O., 2007. Differential Abilities of Capsuled and non
Capsulated Staphylococcus aureus Isolates from diverse agr group to
mammary Epithelial Cells. American Society for microbiology.
Chairul, Erlinda, M., Handoyo, S., dan Chairul, S .M., 1998.Skrining Fitokimia dan
analisis komponen kimia ekstra batang benalu teh, Scurrula atropurpurea,
Warta Tumbuhan Obat Indonesia, Kelompok Kerja Nasional Tumbuhan Obat
Indonesia, Jakarta, 4, 5-8.
Clements, J. D., 1997. Medical microbiology lecture Notes-food Poisoning.Tulane
University Medical School.
<http//www.mcl.tulane.edu/clementslab/page/lecture/badfood/html>
Departemen Kesehatan RI., 1997. Farmakope Indonesia.Jakarta,
Elavazhagan, T., and Arunachalam, K. D., 2010. Phytochemical and Antibacterial
Studies of Seed Extracts of MemecylonEdule. Inter. J. Engin. Sci. Technol.,
2(4): 498-503.http://www.ijest.info/docs/IJEST10-02-04-25.pdf [1.
Eyob, S., Martinsen, B. K., Tsegaye, A., Appelgren, M., and Skrede, G., 2008.
Antioxidant and Antimicrobial activities of Extract and Essential Oil of
Korarima (Aframomum corrorima (Braun) P. C. M. Jansen). Afr.
J.Biotechnol.,7:2585-
2592.htpp://www.academicjournals.org/AJB/abstracts/abs2008/4Aug/Eyob%2
0et%20al.htm.
Foster, T. J., 2004. Staphylococcus. Medmicro, Chapter 12.
Grahame-Smith, D.G. and Aronson, J.K., 1985.Oxford Textbook of Clinical
Pharmacology and Drug Therapy. Oxford University Press, Oxford.
Gur, S, Turgut-Balik, D., Gur, N., 2006. Antimicrobial Activities and SomeFatty Acids
of Turmeric, Ginger Root and Linseed Used in theTreatment of Infectious
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
104
Diseases. World J. Agric. Sci., 2(4), 439-
442.http://www.idosi.org/wjas/wjas2(4)/12.pdf.
Gusviani, W., Gana, A., dan Sukrasno, 2002.Kandungan Kuersitrin pada Beberapa
Jenis Benalu. Skripsi, ITB, Bandung
Haraldson, I., and Jonsson, O. 1984. Histopathology and Pathogenesis of Mouse
Mastitis Induced with Staphylococcus aureus Mutans. J. Comp. Path., 94, 183-
189.
Hembing, W.H.M., 1996. Tanaman Obat Berkhasiat Indonesia.Jilid 1. Pustaka Kartini,
Jakarta, 1-2.
Jagtap, N. S., Khadabadi, S. S., Ghorpade, D. S., Banarase, N. B., Naphade, S. S., 2009.
Antimicrobial and Antifungal Activity of Centella asiatica (L.)Urban,
Umbiliferaceae. Research J. Pharm. Tech., 2(2), 328-
330.http://rjptonline.org/RJPT_2(2)%202009/23-237.pdf.
Jawetz, E., Melnick, J. L. and Adelberg, E. A., 1986. Review of Medical Microbiology (
Mikrobiologi untuk profesi Kesehatan, alih bahasa : Bonang, G dan Tony, H).
Edisi Ke 16. Cetakan IV. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 239-244.
Jawetz, E., Melnick, J.L.,and Adelberg, E.A.,2001.Mikrobiologi Kedokteran Edisi 20.
Penebit Buku Kedokteran EGC.Jakarta
Larbrier, M.and Loeclerco, B., 1992. Nutrition and Feeding Poultry.Nottingham
University Press.
LeLoir, Y., Baron, F., and Gautier, M., 2003. Staphylococcus aureus and food
poisoning. Gene. Mol. Res.2(1), 63-76.
Levinson, W., and Jawetz, E., 2003. Medical Microbiology & Immunology:
Examination & Board Review. 7th ed. McGraw-Hill Companies Inc.
Singapore. 91 - 95, 437.
Merchant, I.A.and Parker, R. A., 1961.Veterinary Bacteriology dan Virology.The Iowa
State University Press, Ames, Iowa, United States of America.306-308.
Miller, A. L., 1996. Antioxidant Flavonoids: Structure, Function and Clinical Usage.
Mills, J., Barriere, S.L., and Jawetz, E., 1987. Vaccines, Immunoglobulins &Other
Complex Biologic products, dalam B.G. Katzung (ed.): Basic and Clinical
Pharmacology. Appleton & Lange, Norwalk, 3rd
. ed. 590-601.
Nelson, W. and Nickerson, S., 1991. Mastitis Counter Attack. Babson Bros.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
105
Ohashi, K, et al., 2003.Cancer Cell Invasion Inhibitory Effects of Chemical
Constituentsin the parasitic Plant Scurrula
artopurpurea(Lorantaceae).Chem.Pharm.Bull.51(3), 343-345.
Okigbo, R. N., Anuagasi, C.L., Amadi, J. E., Ukpabi, U. J., 2009. Potentialinhibitory
effects of some African tuberous plant extracts onEscherichia coli,
Staphylococcus aureus and Candida albicans. Inter.J. Integr. Biol., 6, 91-98.
Oliver, S. P., 2000. Mastitis in Heifers: Prevalence, Strategy for Control during the
Periparturient Period, and Economic Implications. Proceeding British Mastitis
Conference. Institute for Animal Health/Milk Development Council. 1 - 13.
Padli,2010. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Benalu Teh (Scurrula
Atropurpurea (Bi) Dans.) Terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus
aureus Serta Uji Toksisitas Terhadap Artemia Salina Leach. Thesis,
Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Quinn, P. J., Markey, B. K., Carter, M. E., Donnelly, W. J. and Leonard, F. C., 2002.
Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Publishing. USA.
43 - 46, 465 - 475.
Roth, J.A., 1988. Virulence Mechanism of Bacterial Pathogens. American Society of
Microbiology. Washington, D. C. 99.
Salasia, S. I. O, Wibowo, M. H., and Khusnan, Z. 2005.KarakterisasiFenotipeIsolat
Staphylococcus aureusdari Sampel SusuSapiPerah Mastitis Subklinis. J. Sain
Vet., 23, 72-77. htpp://jvs.ugm.ac.id/pdf/vol232/Isrina.pdf.
Samy, R. P., and Gopalakrishnakone, P., 2008. Therapeutic Potential of Plants as Anti-
microbials for Drug Discovery. eCAM, 1-12.
htpp://ecam.oxfordjournals.org/cgi/reprint/nen036v1.
Schroeder, J. W., 1997. Mastitis Control Programs: Bovine Mastitis and Milking
Management. North Dakota State University Agriculture and University
Extension. USA.
Sherris, J., 1984. Staphylococcus in Medical Microbiology and Introduction. Sherris, J.
C., Ryan, K. J., Roy, C. G., Plorde, J., Coray, L., Spizizen, J. (Editors).
Elsevvir Science Publishing Co., Inc. New York.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
106
Simanjuntak, P., Parwati, T., Lenny, L. E., Tamat, S., dan Murwani, R., 2004. Isolasi
dani Identifikasi senyawa antioksi dan dari ekstrak benalu teh, Scurrula
oortiana(Korth) danser (Lorantaceae).J Ilmu Kefarmasian Indonesia. 2. 1, 6-9.
Subronto., 2003. Ilmu Penyakit Ternak (Mamalia) I. Edisi Kedua. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta. 309 - 351.
Sudarwanto, M., 1999. Usaha Peningkatan Produksi Susu Melalui Program
Pengendalian Mastitis Subklinis. Orasi Besar Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu
Kesehatan Masyarakat Veteriner. FKH IPB. Bogor
Tambunan, R. M., Bustanussalam, P., Simanjuntak, dan Muwarni, R., 2003. Isolasi dan
identifikasi kafein dalam ekstrak air daun benalu teh, Scurrula junghunii,
Loranthaceae. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia vol. 1 (2), 16-19.
Tarverna, F., Armando, Renata, N., Alfonso, Z., Simona, N., Severino, R., and Gabriela,
T., 2007. Characterization of Cell Wall Assosiated Protein of A
Staphylococcus aureus Isolated from Bovine Mastitis Case by a Proteomic
Approach. J. Vet. Microbiol.119, 240-247.
Todar, K., 2005. Bacteriology. Staphylococcus. 330Homepage lecture topics.
http://www.bact.wisc.edu/bact3330/lecturestaph
Waranustuti, V., 2009. Resistensi Staphylococcus aureus Asal Manusia, Susu Sapi
Perah dan Susu Kemasan Terhadap Berbagai Antibiotika. Skripsi Sarjana
Kedokteran Hewan, FKH, UGM.
Warsa, C. U., 1994. Kokus Positif Gram Dalam Mikrobiologi Kedokteran. Binarupa
Aksara. Jakarta. 103-111.
Westh, H., Zinn, C. S., Rosdahl, V. T., 2004. An International MulticenterStudy of
Antimicrobial Consumption and Resistance in Staphylococcus aureus Isolates
from 15 Hospitals in 14 Countries.Microbial Drug Resistance., 10: 169-
176.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15256033
Winarno, M. W., Sundari, D., dan Nurtami, B. 2000. Penelitian Aktivitas Biologik Infus
Benalu.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
107
SELEKSI POPULASI F2 TANAMAN KAKAO (Theobroma cacao L.)
BERDASARKAN SIFAT BUAH
Imam Wibisono1, Taryono
2, Nasrullah
2
1 Mahasiswa Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian UGM
2 Staf Pengajar Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian UGM
ABSTRACT
Cocoa is a perrenial cross pollinated crop with self incompatible characteristic.
Cocoa population propagated generatively consequently showed heterogenity and
therefore breeding activity could be carried out using such segregating population. The
selection product further could be used both as breeding and vegetatively propagation
materials.
Three hundred outstanding F2 cocoa trees of unknown parents noted by field
worker as well as five trees each of cocoa clones i.e. RCC 70, RCC 71, RCC 73, and
KKM 4 located in Segayung Utara unit of PT Pagilaran were used in the study.
Following company practice, pod – if available – were picked from each tree for six
times at 14-day interval. Records on pod and seed characteristics were taken on a
random sample of single pod at each harvest.
Repeated measure analysis showed that despite the three hundred F2 cocoa trees
have been selected already, the variability wass still larger than that among trees
clonally propagated ones. It indicated that selection is still possible to be practiced with
repeatability ranged from medium to high depending on the characteristics.
Independent culling selection with respect to pod length, pod diameter, thick of rind,
pod fresh weight, seed number per pod, and dry weight of individual seed, with their
mean of clone characteristicss minimum value of the first four, and 40 seeds of 1 g each
per pod as threshold level yielded five outstanding trees.
Keyword : Cocoa (Theobroma cacao L.), Selection, Repeatability
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
108
PENDAHULUAN
Kakao merupakan salah satu komoditas utama program revitalisasi perkebunan
di Indonesia. Target pengembangannya hingga tahun 2010 mencapai 200 ribu ha
dengan rincian program peremajaan 54 ribu ha, rehabilitasi tanaman tua 36 ribu ha, dan
perluasan areal 110 ribu ha. Pada tahun 2010,Indonesia menjadi negara dengan produksi
kakao terbesar kedua di dunia dengan produksi mencapai 844.626 ton.Produksi kakao
Indonesia ini masih di bawahproduksi kakao Pantai Gading yang mencapai 1.380.000
ton.
Tanaman kakao di Indonesia sebagian besar berasal dari bibit asal biji yang telah
tua umurnya.Rata-rata tanaman kakao berusia di atas 20 tahun.Kondisi tanaman yang
berasal dari biji menyebabkan hasil yang didapatkan beragam karena kakao bersifat
menyerbuk silang (Hafid et al., 2009).Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan
penyelesaian cepat dengan melakukan intensifikasi melalui penanaman kultivar unggul
baru yang memiliki produktivitas tinggi, berkualitas biji baik dan tahan terhadap OPT
utama, serta menerapkan teknik budidaya pertanian berkelanjutan.
Pada tanaman tahunan seperti kakao kegiatan pemuliaan tanaman untuk
mendapatkan tanaman kakao yang memiliki sifat genetis unggul melalui persilangan
dan perbanyakan generatif relatif sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Suatu
individu kakao yang berasal dari biji baru akan berbuah saat memasuki tahun ke-3
sampai ke-5.
Metode seleksi pohon induk asal biji menjadi salah satu tahap pemuliaan
tanaman kakao yang direkomendasikan untuk menghasilkan klon unggul baru tanaman
kakao.Hasil seleksi ini nantinya dapat diperbanyak menggunakan metode sambung,
okulasi, ataupun untuk menghasilkan bibit embriogenesis somatik yang siap tanam.
PT. Pagilaran milik Yayasan Fakultas Pertanian UGM memiliki kebun yang
cukup luas yang sebagian lahannya yaitu Kebun Segayung digunakan untuk
membudidayakan berbagai kultivar kakao asal biji dan klon unggul (Anonim,
2011c).Penelitian ini mencoba melakukan seleksi pohon induk asal biji menggunakan
klon kakao unggul asal sambung pucuk sebagai pembanding.
Tujuan
Mengetahui hasil individu kakao yang potensial digunakan sebagai induk
perbanyakan vegetatif maupun bahan persilangan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
109
Hipotesis
Terdapat tanaman-tanaman asal biji yang memiliki kualitas dan kuantitas hasil
yang sama atau lebih baik dari tanaman asal klon sehingga potensial untuk
dikembangkan sebagai induk perbanyakan vegetatif maupun bahan persilangan.
MATERI DAN METODE
Penelitian dilakukan di PT Pagilaran unit produksi segayung utara pada bulan
Oktober 2011 – Januari 2012. Bahan yang digunakan adalah tanaman kakao identitas
biji tidak diketahui tetuanya (asal biji F2) sebanyak 300 nomor dan tanaman kakao asal
sambung pucuk sebanyak 4 klon (RCC 70, RCC 71, RCC 73, KKM 4) sebanyak
masing-masing 5 pohon .
Pengamatan dilakukan terhadap sifatbuah pada masing-masing individu yang
dipanen selama 6 kali sesuai daur pemanenan di PT. Pagilaran dengan jarak panen 14
hari sekali. Pada setiap pohon masing-masing diambil satu buah kakao untuk diamati.
Waktu pemanenan digunakan sebagai ulangan. Pada individu yang pemanenan buahnya
kurang dari 6 kali, jumlah ulangan dalam penelitian disesuaikan dengan jumlah waktu
pemanenan buah.Sifat kuantitatif yang diamati meliputi panjang buah, diameter buah,
tebal kulit buah, bobot segar buah, bobot segar dan bobot kering polong, jumlah biji per
buah, bobot segar biji per buah, bobot kering biji per buah, dan bobot kering biji per
butir. Sifat kualitatif meliputi warna buah dan bentuk buah.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak sempurna dengan model analisisYijk
= µ + i + βij+ eijkuntuk populasi tanaman asal klon dengan Yijk= nilai sifat klon ke-i
pada pohon ke-j, dan waktu panen ke-k; µ= rerata umum; i = pengaruh klon ke-i; βij =
pengaruh pohon ke-j dari klon ke-i; dan eijk= pengaruh waktu panen ke-k dari pohon ke-
j dari klon ke-i. Pada populasi tanaman asal biji model analisis yang digunakan adalah
Yik = µ + βi + eik, dengan Yijk= nilai sifat pohon ke-i dan waktu panen ke-k; µ = rerata
umum; βi= pengaruh pohon ke-i; dan eik= pengaruh waktu panen ke-k dari pohon ke-i.
Dengan asumsi kedua lahan memberikan hasil yang homogen, dapat dilakukan
pendugaan komponen varian genotipe (𝜎𝑔2) dan varian fenotip (𝜎𝑃
2) penyusun populasi
asal biji melalui varian lingkungan tumbuh (𝜎𝑒𝑔2 ) klon dan varian lingkungan umum
(𝜎𝑒𝑠 2
(t)). Pada penelitian dilakukan pendugaan terhadap nilai keberulangan (R), nilai
heritabilitas (H), serta seleksi menggunakan independent culling level.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
110
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Varian
Analisis varian terhadap sifat panjang buah, diameter buah, tebal kulit buah,
bobot segar buah, bobot segar polong, jumlah biji, bobot segar biji per polong, bobot
kering biji per polong, serta bobot kering biji per butir antar klon menunjukkan terdapat
perbedaan nyata.
Tabel 1.Sifat buah kakao asal klon
Klon Panjang
buah (cm)
Diameter
Buah (cm)
Tebal kulit
buah (cm)
Bobot
segarbuah (g)
Bobot segar
Polong (g)
Bobot kering
Polong (g)
RCC 70 18,20 ± 0,79
b 7,82 ± 0,51 b
1,40 ±
0,22a 474,86 ± 4,01c
435,46 ± 3,86
b
42,29 ± 1,21
d
RCC 71 18,03± 0,23
b 9,10 ± 0,13 a
1,41 ± 0,22
a
683,19 ± 25,49
a
584,47 ± 29,43
a
68,93 ± 0,54
a
RCC 73 20,04± 0,35
a 7,97 ± 0,12b
1,24 ±
0,02b
525,20 ± 17,26
b
412,14 ±
17,02b
58,90 ± 1,46
b
KKM 4 15,67± 0,10
c 8,68 ± 0,05a
1,49 ± 0,04
a
500,59 ±
8,43bc 421,60± 8,25 b
52,52 ± 0,64
c
Keterangan :Angka-angka yang disertai huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat
beda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5 %
Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa klon RCC memiliki ukuran buah yang
paling panjang yaitu 20,04 cm, akan tetapi ukuran diameter buah dan tebal kulitnya
lebih kecil jika dibandingkan dengan klon lainnya. Buah dengan ukuran diameter buah
terbesar ditunjukkan oleh klon RCC 71 yaitu 9,096 cm dan KKM 4 yaitu 8,68 cm.Klon
KKM 4 juga memiliki nilai kulit buah tertinggi yaitu 1,49 cm.RCC 71 menunjukkan
bobot segar buah tertinggi yaitu 683,19 gram serta bobot segar polong tertinggi yaitu
584,47 gram. Bobot segar buah dan bobot segar polong yang tinggi menunjukkan
bahwa klon RCC 71 memiliki kandungan biomassa dan air pada buah yang tinggi.
Buah kakao memiliki bentuk yang beragam dan erat kaitannya dengan jumlah
biji serta ukuran biji yang dihasilkan. Buah kakao yang matang dapat diketahui dari biji
yang telah lepas dari polongnya dengan cara menggoyang buah. Dalam setiap buah
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
111
biasanya terdapat 30-50 biji bergantung pada jenis klonnya. Beberapa jenis kakao
menghasilkan jumlah buah yang banyak akan tetapi bijinya kecil (Siregar et al. 2007).
Tabel2.Jumlah biji, bobot segar dan bobot kering biji per polong, dan bobot kering biji per
butir kakao asal klon.
Klon Jumlah
biji/polong
Bobot segar
Biji/polong
(gr)
Bobot kering
Biji/polong (g)
Bobot kering
biji/butir (g)
RCC 70 45,57 ± 1,23 a 39,40 ± 1,07 d 33,17 ± 0,94 c 0,72 ± 0,14 d
RCC 71 44,44 ±0,94 a 98,71 ± 5,66 b 49,59 ± 1,83 a 1,11 ± 0,03 a
RCC 73 40,53±0,82 b 113,06 ± 2,83a 33,57 ± 0,77 c 0,84 ± 0,02 c
KKM 4 40,00±0,61 b 78,96 ± 4,78 c 36,24 ± 1,13 b 0,91± 0,03 b
Keterangan : Angka-angka yang disertai huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat
beda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5 %.
Jumlah biji merupakan kriteria penting yang diperhatikan dalam memilih klon
kakao unggul. Tabel 2 menunjukkan bahwa klon RCC 70 dan RCC 71 memiliki jumlah
biji terbanyak yaitu 45 dan 44 biji per polong.Bobot segar biji per polong tertinggi
ditunjukkan oleh klon RCC 73 yaitu 113,06 cm. Bobot segar biji yang tinggi ini
disebabkan terdapat banyak kandungan pulpa dan air yang melapisi permukaan
biji.Kakao dengan bobot kering per polong tertinggi ditunjukkan oleh klon RCC 71
yaitu 49,59 gram per polong, begitu juga dengan bobot kering biji per butir yaitu 1,11
gram per butir. Biji kakao yang besar diduga memiliki kandungan lemak yang tinggi.
Kandungan lemak yang tinggi ini yang menjadi pertimbangan dalam pengolahan kakao
sebagai bahan baku industri seperti kosmetik, makanan, dan minuman. Dari pengamatan
ini klon RCC 71 dapat dikategorikan sebagai individu superior berdasarkan Monteiro
(2009) karena memiliki jumlah biji 40 butir per polong atau lebih dan bobot kering per
butir gram atau lebih.
Pada petak asal biji, hasil anova terhadap panjang buah, diameter buah, tebal
kulit buah, bobot segar buah, bobot segar polong, bobot kering polong, jumlah biji per
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
112
polong, bobot biji segar per polong, bobot biji kering per polong, dan bobot biji kering
per butir antar pohonmenunjukkan terdapat perbedaan nyata (Pr< 0,0001).
Tabel 3.Jumlah kuadrat dan kuadrat tengah tanaman kakao asal biji
Sumber Keragaman Jumlah kuadrat Kuadrat tengah
Pr > F Pohon Sesatan Pohon Sesatan
Panjang 7938,69 11411 26,55 8,71 <,0001
Diameter 633,52 522,07 2,12 0,39 <,0001
Tebalkulit 111,62 331,07 0,37 0,25 <,0001
Bobot segarbuah 15835542 17369618 52961,68 13259,25 <,0001
Bobot segar polong 13239935 15355842 44280,72 11722,02 <,0001
Bobot keringpolong 325267 228585 1087,85 174,4924 <,0001
Jumlahbiji 24466 55558 81,83 42,41 <,0001
Bobot segar
biji/polong 372090 697218 1244,45 532,23 <,0001
Bobot
keringbiji/polong 80321 125899 268,63 96,11 <,0001
Bobot kering biji/butir 38,17 54,94 0,13 0,04 <,0001
db pohon = 299, db error = 1310
Perbedaan nyata yang terdapat pada populasi tanaman asal biji dipengaruhi oleh
keragaman sifat yang tinggi antara pohon yang satu dengan pohon yang
lainnya.Keragaman fenotipe merupakan keragaman yang timbul akibat adanya
keragaman genotipe dan interaksinya dengan lingkungan.
Pada sifat-sifat yang keragamannya tinggididuga terdapat individu-individu
yang memiliki potensi hasil lebih tinggi dibandingkan tanaman kakao asal klon.Dengan
melihat besar peran interaksi genotipe dan lingkungan mikro yang berpengaruh terhadap
keragaan buah, dapat dipertimbangkan peluang kemunculan sifat yang sama di masa
yang akan datang pada pohon-pohon asal biji yang nantinya potensial terpilih.
B. Keberulangan
Keberulangan dapat digunakan untuk menduga berulangnya kemunculan sifat
tertentu suatu tanaman pada masa hidupnya.Karena genotipe pada individu tanaman
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
113
tahunan tidak berubah selama hidupnya, maka dalam pengamatan berulang pengaruh
genotipe yang sama berlaku, sedang perubahan keragaman yang timbul antara beberapa
pengamatan disebabkan oleh perubahan dalam pengaruh faktor lingkungan yang
berbeda.
Menurut Simmonds (1981) dalam konteks pemuliaan tanaman, ripitabilitas lebih
dekat hubungannya dengan heritabilitas dalam arti luas dari sifat antar grup seperti klon
atau lini murni.Heritabilitas dalam arti luas hanya dapat menjelaskan berapa bagian
antar keragaman fenotipe yang disebabkan oleh pengaruh genetik dan bagian pengaruh
faktor lingkungan, namun tidak dapat menjelaskan proporsi keragaman fenotipe pada
tetua yang dapat diwariskan pada turunannya.
Pada kondisi lingkungan yang sama, komponen varian penyusun populasi yaitu
varian lingkungan permanen (𝜎𝑒𝑔2 ), varian lingkungan sementara (𝜎𝑒𝑠
2(t)), varian genotipe
(𝜎𝑔2), varian fenotipe (𝜎𝑝
2) dapat diketahui dengan menggabungkan nilai varian pada
tanaman kakao asal biji dengan nilai varian pada tanaman kakao asal klon dengan
asumsi varian lingkungan sama.
Tabel 4. Komponen varian, nilai keberulangan, dan nilai keterwarisan dalam arti luas
sifat tanaman kakao asal biji
Sifat 𝜎𝑒𝑔2 𝜎𝑒𝑠
2(t) 𝜎𝑔
2 𝜎𝑝2
Keberulangan
(R)
Keterwarisan
(H) dalam
arti luas
Panjang -
0,0048 8,27 3,325 11,595 28,67% 28,67%
Diameter 0,0332 0,398 0,287 0,718 44,60% 39,98%
Tebal Kulit 0,0051 0,237 0,017 0,26 8,64% 6,67%
Bobot segar
buah
-
1226,2 12983,2 7398,6 20381,8 36,30% 36,30%
Bobot segar
polong
-
1500,6 11633,3 6067,4 17700,7 34,28% 34,28%
Bobot kering
polong
-
3,5133 164,998 170,206 335,204 50,78% 50,78%
Jumlah biji 2,873 39,042 4,472 46,387 15,84% 9,64%
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
114
Bobot segar
biji /polong
-
72,167 530,49 132,724 663,214 20,01% 20,01%
Bobot kering
biji/polong -6,449 93,336 32,151 125,487 25,62% 25,62%
Bobot kering
biji/butir
-
0,0018 0,0407 0,0159 0,0566 28,21% 28,21%
*jika nilai varian minus (-) dianggap = 0
Pada sifat panjang buah, keberulangan dan keterwarisan dalam arti luas kakao
bernilai sama yaitu 28,67 % yang termasuk kategori sedang, demikian juga dengan sifat
bobot segar buah (36,30%), bobot segar polong (34,28%), bobot segar biji (20,01%),
bobot kering biji per buah (25,62 %), serta bobot kering biji per butir (28,21%). Pada
sifat bobot kering polong kakao, nilai keberulangan dan keterwarisan dalam arti
luastermasuk kategori tinggi yaitu 50,78 %.
Pada sifat diameter buah, nilai keterwarisan dalam arti luas kakao termasuk
kategori sedang yaitu 39,98 %, sedangkan nilai keberulangannya termasuk kategori
tinggi yaitu 44,6 %. Sifat tebal kulit buah menunjukkan nilai keterwarisan dalam arti
luas yang rendah yaitu 6,67 %, demikian juga dengan nilai keberulangannya 8,64 %.
Sifat jumlah biji juga memiliki nilai keterwarisan dalam arti luas dan keberulangan yang
rendah yaitu 9,64% dan 15, 84 %.
Nilai heritabilitas atau keterwarisan selalu lebih rendah daripada nilai
keberulangan karena nilai keberulangan merupakan batas atas dari nilai heritabilitas, hal
ini sesuai dengan pendapat Falconer (1960) dalam Dakhlan et. al. (2008). Beberapa sifat
seperti panjang buah, bobot segar buah, bobot segar polong, bobot kering polong, bobot
segar biji per buah, bobot kering biji per buah, dan bobot kering biji per butir memiliki
nilai heritabilitas dan nilai keberulangan yang sama dikarenakan penduga varian
lingkungan permanennya 𝜎𝑒𝑔2 minus (-).
Pada sifat-sifat kakao dengan nilai varian lingkungan permanen 𝜎𝑒𝑔2 yang minus
(-), nilai keberulangan sama dengan nilai heritabilitas dalam arti luas𝜎𝑔2 𝜎𝑝
2 karena
varian 𝜎𝑒𝑔2 dianggap = 0. Artinya, untuk sifat yang diamati tersebut, keragaman yang
terjadi lebih diakibatkan oleh faktor lingkungan sementara atau varian karena perbedaan
waktu pemanenan daripada faktor lingkungan permanen atau varian karena perbedaan
titik tanam.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
115
Nilai keberulangan yang tinggi menggambarkan besarnya kemungkinan
berulangnya nilai sifat yang samapada waktu yang berbeda dari individu yang sama
sepanjang hidupnya. Sebaliknya nilai keberulangan yang rendah menggambarkan kecil
kemungkinan munculnya sifat yang sama pada waktu yang berbeda dari individu
tersebut.
Pada sifat tebal kulit buah dan jumlah biji nilai keberulangan tergolong kategori
rendah, hal ini menunjukkan bahwanilai kedua sifat tersebut beragam antar periode
pemanenan, sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan kakao dengan jumlah biji
dan tebal kulit buahyang sama pada tiap pemanenan. Berdasarkan pengamatan kualitatif
di lapangan, faktor lingkungan sementara yang dicurigai memberikan pengaruh
terhadap keragaman jumlah biji ini diantaranya adalah adanya kegagalan pembentukan
biji pada saat perkembangan buah maupun kerusakan biji akibat serangan hama PBK
pada beberapa buah kakao. Sedangkan faktor lingkungan sementara yang dicurigai
memberikan pengaruh terhadap tebal kulit buah adalah perubahan kadar air di
lingkungan pada saat pengukuran. Pada saat kondisi kadar air normal, pengukuran tebal
kulit buah dapat dilakukan secara optimal. Namun, pada kondisi lingkungan kering
terjadi transpirasi pada buah sehingga ukuran kulit buah menyusut, akibatnya
pengukuran yang dilakukan tidak tepat.
Pada sifat bobot kering polong dan diameter buah, nilai keberulangan tergolong
dalam kategori tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa nilai pada kedua sifat tersebut
seragam antar periode pemanenan, sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan
kakao dengan diameter buah dan bobot kering polong yang sama pada setiap
pemanenan. Sifat diameter buah penting diperhatikan karena diduga berpengaruh
terhadap besarnya biji yang dihasilkan, sedangkan sifat bobot kering polong kurang
begitu penting karena tidak berhubungan langsung dengan hasil biji.
C. Seleksi Tanaman Kakao Asal Biji
Seleksi menggunakan independent culling level dilakukan berurutan terhadap
enam sifat penting yaitu panjang buah, diameter buah, tebal kulit buah, bobot segar
buah, jumlah biji, dan bobot kering biji per butir. Sifat-sifat tersebut digunakan dalam
seleksiindependent culling level karena diduga memiliki peran penting terhadap
lahirnya buah kakao unggul.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
116
Batas pemenggalan terhadap sifat panjang buah, diameter buah, tebal kulit buah,
bobot segar buah kakao terpilih berdasarkan nilai sifat minimum pada klon, sedangkan
sifat jumlah biji dan bobot kering biji per butir sesuai kriteria biji superior oleh
Monteiro (2009) yaitu 40 butir per polong dan bobot kering biji 1 gram per butir.
Pemilihan pertama dilakukan terhadap sifat panjang buah kakao dengan batas
pemenggalan 15,67 cm setara dengan rerata panjang buah dari klon KKM 4. Dari
pemilihan ini diperoleh 60 pohon kakao. Selanjutnya dari populasi terpilih dilakukan
pemilihan kembali terhadap sifat diameter buah dengan batas pemenggalan 7,82 cm
atau setara dengan rerata diameter buah RCC 70. Dari pemilihan kedua ini diperoleh 37
individu kakao.
Pemilihan dilanjutkan pada tahap ketiga terhadap sifat tebal kulit buah dengan
batas pemenggalan 1,24 cm setara dengan tebal kulit klon RCC 73, dari pemilihan ini
diperoleh 17 individu kakao. Tahap keempat terhadap sifat bobot segar buah dengan
batas penggal 474,86 gram atau setara rerata bobot segar klon RCC 70 menunjukkan
terdapat 10 pohon asal biji yang terpilih memiliki bobot segar lebih > klon yang
diamati.
Pemilihan kelima dilakukan terhadap sifat jumlah biji kakao sesuai dengan
kriteria biji superior Monteiro et al. (2009) yaitu batas pemenggalan 40 biji per buah.
Pada penelitian ini, semua kakao yang telah terpilih di tahap sebelumnya ternyata
memiliki jumlah bijisama dengan 40 atau lebih. Tahap berikutnya adalah pemilihan
berdasarkan bobot kering biji per butirnya, batas penggal ditentukan sesuai kriteria biji
superior yaitu lebih daripada 1 gram.
Tabel 5. Pohon terpilihasal biji berdasarkan independentculling level
No. Pohon Panjang
buah (cm)
Diameter
buah (cm)
Tebal kulit
(cm)
Bobot segar
biji (g)
Jumlah
biji
Bobot kering
biji/butir (g)
ph96 21,28 8,22 1,37 651,00 44,17 1,16
ph50 17,62 9,66 1,38 654,80 40,17 1,13
ph28 17,47 8,82 1,37 596,00 43,67 1,04
ph172 16,74 8,34 1,28 475,33 40,83 1,03
ph279 15,96 9,02 1,24 521,50 43,00 1,22
Batas
penggal 15, 67 7,82 1,24 474,86 40 1,00
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
117
Rerata
terpilih 17,81 8,81 1,33 579,73 42,37 1,12
Rerata awal 15,10 7,67 1,06 403,27 39,56 0,92
Dari pemilihan yang terakhir diperoleh lima nomor pohon kakao yang memiliki
keunggulan dalam sifat-sifat tersebut. Kakao yang terpilih memiliki panjang buah yang
ukurannya berkisar antara 15,96 – 21,28 cm, diameter buah yang berkisar 8,22 – 9,66
cm, serta tebal kulit buah berkisar antara 1,24 - 1,38 cm.
Pohon kakao dengan nomor pohon 96 memiliki rerata jumlah biji terbanyak
yaitu 44 biji/buah, sedangkan kakao dengan rerata bobot kering biji per butir terbesar
ditunjukkan oleh kakao dengan nomor pohon 279 yaitu 1,22 g/butir. Kakao dengan
nomor pohon 50 memiliki diameter buah, tebal kulit, dan bobot segar buah yang paling
tinggi berturut-turut 9,66 cm, 1,38 cm, dan 654,8 g/buah. Kakao yang memiliki panjang
buah terbesar ditunjukkan oleh kakao dengan nomor pohon 96 yaitu 21,28 cm.
Rerata populasi meningkat karena pada populasi tanaman yang telah diseleksi
yang tersisa hanya tanaman-tanaman terpilih yang memiliki sifat unggul diatas rerata
populasi awalnya.Sedangkan varian populasi berkurang karena populasi yang terpilih
keragamannya terbatas dari individu-individu yang memiliki sifat unggul saja.
Penggunaan batas penggal yang setara dengan nilai klon tidak akan mengubah
hasil dari pohon-pohon yang terpilih meskipun tahapan seleksinya diubah susunannya.
Sedangkan apabila menggunakan persentase sifat di setiap seleksi, hasil tanaman
terpilih dapat berbeda jika pemberian persentase batas penggalnya diubah, atau tahapan
seleksinya diubah susunannya.
Penampilan suatu pohon yang rendah mungkin bukan dikarenakan pohon
tersebut berkemampuan rendah, tetapi karena faktor lingkunganlah yang membuat
pohon tersebut berkemampuan lebih rendah dari pohon lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa tanggapan fenotipe terhadap perubahan lingkungan tidak sama untuk semua
genotipe karena disebabkan adanya interaksi genotipe dengan lingkungan (Soemartono,
et al., 1992).
D. Morfologi Buah Tanaman Kakao Terpilih
Berdasarkan panduan pencanderaan buah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian
Kopi dan Kakao Jember, tanaman kakao asal biji yang terpilih sebagian besar memiliki
warna hijau.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
118
Tabe 6. Morfologi buah tanaman kakao asal biji terpilih
Nomor
Pohon Warna
Morfologi Buah
Bentuk
buah Leher botol Ujung buah Alur
Tekstur
buah
ph96 Hijau jorong Sedang lancip dalam kasar
ph50 Hijau jorong Sedang tumpul dangkal kasar
ph28 Hijau jorong Sedang tumpul dangkal kasar
ph172 Hijau jorong Sedang tumpul dangkal licin
ph279 Hijau jorong Samar tumpul dangkal kasar
Laode (2004) menjelaskan bahwa tanaman yang memiliki bentuk buah yang
bulat, lonjong, atau jorong, pangkal buah tumpul, kulit buah yang licin, alur buah
dangkal, dengan rata-rata kulit buah yang tebal dan rapat massa sklerokarp yang tinggi
tidak disukai oleh hama PBK karena hama tersebut kesulitan untuk meletakkan
telurnya. Meskipun hama PBK berhasil meletakkan telurnya pada buah yang licin dan
beralur dangkal tersebut, maka telurnya akan lebih mudah jatuh dengan sendirinya atau
terkena hujan. Berbeda dengan buah yang kasar dan beralur dalam akan lebih mudah
dihinggapi hama PBK dan ditempati untuk meletakkan telurnya.
Ph 96
Ph 50
Ph 28
Ph 172
Ph 279
Gambar 4.1 Buah kakao terpilih hasil independent culling level
Jika mengacu pada penelitian Laode (2004), pohon terpilih yang diduga
memiliki ketahanan terhadap PBK berdasarkan karakter morfologinya adalah buah
dengan nomor pohon 172, karna memiliki alur yang dangkal, dan tekstur buah yang
licin. Akan tetapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar
ketahanan buah kakao terhadap serangan PBK agar data yang didapatkan lebih akurat.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
119
Dalam penelitian belum dilakukan pengukuran terhadap serangan PBK sehingga
tidak diketahui dengan pasti berapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh PBK pada
masing-masing pohon. Pada penelitian ini hanya dilakukan pencatatan buah mana yang
terserang PBK pada setiap pemanenan.
KESIMPULAN
1. Nilai keberulangan sifat diameter buah dan bobot kering polong termasuk kategori
tinggi;nilai keberulangan sifat panjang buah, bobot segar buah, bobot segar polong,
bobot segar biji, bobot kering biji per buah, dan rerata bobot kering biji per butir
termasuk kategori sedang;dannilai keberulangan sifat tebal kulit buah dan jumlah biji
termasuk kategori rendah.
2. Pohon kakao asal biji yang memiliki potensi digunakan sebagai induk perbanyakan
vegetatif maupun bahan persilangan berdasarkan independent culling level adalah
sebanyak 5 individu pohon kakao, yaitu dengan nomor 96, 50, 28, 172, dan 279.
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-nya, penulis dapat
menyelesaikan makalah `SELEKSI POPULASI F2 TANAMAN KAKAO (Theobroma
cacao L.) BERDASARKAN SIFAT BUAH`. Penulis berharap semoga makalah ini
bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada :
1. Dr. Ir. Taryono M.Sc. dan Dr. Ir. Nasrullah. M.Sc. selaku dosen pembimbing yang
telah banyak membimbing penulis dari awal sampai dengan selesai.
2. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil sehingga
penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan proses perkuliahan.
3. Teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi setiap saat.
DAFTAR PUSTAKA
Hafid, H., Lapomi, Z., Branford, R.B., Badcock, S. and Matlick, B.K. 2009. Panduan
AMARTA Untuk Keberlanjutan Kakao, Evaluasi Kebun, Rehabilitasi, dan
Peremajaan. USA. USAID.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
120
Falconer, D.S. 1960.Introduction to Quantitative genetics. The Ronald Press Co.New
York.
Laode, A. 2004.Seleksi dan Karakterisasi Morfologi Tanaman Kakao Harapan Tahan
Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella Snell.). Jurnal Sains dan
Teknologi: 109-122.
Mangoendijojo, W. 2003. Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman. Kanisius.Yogyakarta.
Monteiro, W.R., Lopez, U.V., Clement, D. 2009. Genetic improvement in
cocoa.Dalam”Breeding Plantation Tree Crops (Jain &Priyadarshan). Springer
science : 589 – 626.
Sastrosupadi, A. 1999. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian.
Kanisius.Yogyakarta.
Soemartono, Nasrullah, Hartiko, H. 1992. Genetika Kuantitatif dan Bioteknologi
Tanaman. Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.
Siregar, T.H.S., Riyadi, S., Nuraeni, L. 2007. Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
Coklat. Penebar Swadaya. Jakarta.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
121
PETA FLASH INTERAKTIF SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATAPULAU
MARATUA
Agung Widcha Aulia Rachman
Jurusan Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
Maratua Island is one of the outer islands in the Indonesian region. Located at the east
end of East Borneo. The remoteness and difficult access to remote cause Maratua
Island. but it also makes Maratua awake the nature. The reefs of the island Maratua
very famous among foreign diver. Diver within homegrown while rarely anyone knows.
In addition to the beautiful coral reefs there is treasure that exists only in Maratua
Island. Ie brackish water lake in which there were jellyfish didn‟t sting. And on the
Maratua island there are 3 lakes such Kakaban lake, Hajibuang lake and Tano Bamban
lake. While outside Indoneisa only one piece of the lake as it is on the lake palau pacific
archipelago in Micronesia, but the lake there has been damaged by uncontrolled tourist
traffic. To appreciate the beauty of the island to the outside world Maratua then be
made based interktife flash map an attractive and easy to use. The data used were alos
satellite imagery as a base map, and survey data directly to a location using gps
navigation. For spatial processing used softwere arcgis10 and to interactively display
used adobe flash cs4. Later interactive map created to highlight tourism island Maratua
and gives easy to understand information about the destination tourists who want to
visit
Keywords: interactive flash map, maratua island, maratua tourism.
PENDAHULUAN
Pulau Maratua terletak di sebelah timur Kalimantan Timur, tidak jauh dari
Malaysia dan Filipina. Pulau maratua sendiri merupakan sebuah kecamatan yang baru
berdiri, terdiri dari empat kampung. Kampung Teluk alulu, kampung, Bohe Bukut,
Kampung Payung payung, dan Kampung Bohe Silian. Sebelumnya maratua merupakan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
122
bagian dari kecamatan Pulau Derawan. Pulau maratua memiliki berbagai destinasi
wisata alam baik di darat maupun di laut. Bahkan keindahan kedalaman lautnya sudah
sangat terkenal di kalangan penyelam mancanegara. Sementara potensi wisata di darat
belum banyak dikenal oleh orang di luar pulau Maratua. Sedangkan pendapatan
penduduk maratua dari wisata laut kurang dapat dinikmati. Karena kebanyakan
wisatawan hanya mengunjungi perairan di Maratua sedangkan untuk akomodasinya
mereka mendapatkannya di Pulau Derawan. Oleh karena itu untuk dapat menjadi pelaku
wisata, diperlukan pengembangan pariwisata di darat. Sehingga banyak wisatawan yang
menghabiskan waktu di pulau maratua. Oleh karena itu peningkatan infrastruktur
sebagai penunjang pariwisata di Maratua perlu di sediakan. Hal sudah mulai dirintis
oleh pihak pemerintahan profinsi Kalimantan Timur salah satunya dengan akan
dibangunnya dermaga dan bandara perintis di sana. Selain itu diperlukan sistem
informasi pariwisata yang dapat dengan mudah dimengerti oleh wisatawan. Dan dapat
menunjukan lokasi tiap destinasi wisata yang menarik. Dalam penelitian ini digunakan
softwerearcgis10 melakukan pemrosesan data yang telah dikumpulkan dengan survey
langsung di lapangan. Agar tampilan menarik dan dapat dimengerti oleh orang yang
masih awam, maka digunakanlah softwere adobe flash cs4.
Batasan Masalah
Proses untuk mendata obyek – obyek pariwisata baik wisata alam maupun
budaya yang tersebar di Kabupaten Manggarai Barat. Penerapan GIS unutk mendukung
pendataan potensi pariwisata alam dan budaya yang belum dikembangkan secara
optimal di Kabupaten Manggarai Barat.
Permususan Masalah
Wilayah studi hanya mencakup kecamatan Maratua dan destinasi wisata yang
berada di darat. Peta yang digunakan merupakan hasil digitasi citra satelit ALOS karena
pihak Bakosurtanal tidak memiliki peta Maratua baik yang skala 1 : 25000 maupun 1
:100000. Analisa pengolahan data meliputi lokasi wisata, infrastruktur yang ada dan
rute menuju destinasi wisata yang ada. Hasil dari penelitian adalah berupa peta flash
interaktif pariwisata dan infrastruktur pulau Maratua yang dapat di jalankan di berbagai
platform komputer
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
123
Gambar 1 : citra ALOS sebagai peta dasar
Tujuan
Mengidentifikasi dan menganalisa obyek – obyek wisata di kecamatan Maratua
khusunya wisata alam , menyajikan informasi daerah wisata baik informasi spasial dan
non spasial, membuat analisa jalur jalur yang dapat membantu para wisatawan untuk
mencapai daerah tujuan wisata, membuat Sistem Informasi Geografis yang bertujuan
untuk menginfentarisasi informasi tentang obyek – obyek wisata di kecamatan Maratua.
Manfaat
Member informasi mengenai kawasan wisata alam di kecamatan Maratua yang
dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, pemerintah setempat maupun pengelola tempat
wisata untuk kepentingan bersama.
MATERI DAN METODE
Lokasi penelitian diwilayah Kecamatan Maratua Kabupaten Berau Kalimantan
Timur
Peralatan:
1) Laptop
2) GPS Navigasi
3) Kamera Digital
4) OS Windows 7
5) ArcGIS 10
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
124
6) Microsoft Word 2007
7) Microsoft Excell 2007
8) Adobe Flash CS4
Bahan:
1) Citra satelit ALOS.
2) Data lokasi dan posisi objek - objek wisata
3) Data deskripsi obyek wisata pulau Maratua
Tahap Penelitian
Gambar 2. Diagram alir tahap penelitian (Albertus D Senda Nobe, 2011
Identifikasi masalah, permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana
memperoleh data - data yang diperlukan baik data spasial maupun data non spasial yang
digunakan dalam penelitian pembuatan system informasi geografis untuk
pengembangan pariwisata di kecamatan Maratua.Studi Literatur , bertujuan untuk
mendapat kanreferensi yang berhubungan dengan Penginderaan Jauh, SIG, Potensi
Pariwisata, Dokumentasi dan literature lain yang mendukung baik dari buku, jurnal,
majalah, koran, internet danlain-lain.Pengumpulan data, dilakukan dengan ijin dan
kerjasama dengan beberapa dinas terkait di Kecamatan Maratua. Pengumpulan data,
pada tahapan ini dilakukan pengolahan dari data - data yang telah diambil dari lapangan
dan data penunjang lainnya untuk selanjutnya dilakukan analisa.Tahap analisa, data
yang telah diolah kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga didapatkan suatu hasil
dan kesimpulan yang nantinya digunakan untuk menyusun jurnal.Penyusunan laporan
merupakan tahap akhir dari penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Maratua dan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
125
disajikan dalam bentuk jurnal dan peta interaktif.
Tahap Pengolahan Data
Gambar 3. Diagram alir tahap pengolahan data.
Input data
1) Citra ALOS dengan system koordinat yang
2) Data posisi lokasi – lokasi objek – objek pariwisata yang diperoleh dari
pengukuran dengan GPS Handheld.
3) Data lokasi dan deskripsi sebaran tempat wisata Maratua
4) Dokumentasi obyek – obyek wisata yang diperoleh dari penelitian pribadi.
Pengolahan dan Analisis
Digitasi Citra ALOS
Lang Melakukan import citra ALOS,
kemudian lakukan digitasi dengan softwere Arcgis10
Gambar 4. Hasil digitasi Citra ALOS
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
126
Perancangan SIG
Pembuatan database didalam software
ArcGIS 10 yang berisi tentang infrastruktur dan
lokasi pariwisata Maratua.
Gambar 5. Perancangan GIS
Pembuatan Aplikasi GIS
Setelah perancangan GIS Wisata
Alam kecamatan MaratuaArcMap 10
selesai dibuat maka tahapan selanjutnya
adalah membuat aplikasi interface
kedalam program Adobe Flash CS4 agar
user dapat mengakses dengan mudah dan
dapat digunakan oleh banyak pihak sesuai
dengan kepentingannya masing - masing.
Gambar 6. Penyusunan Aplikasi Interface
Output
Sistem Informasi Geografis Panduan Wisatawa. Hasil akhir dari penelitian ini adalah
GIS mengenai pariwisata alam Kecamatan Maratua dapat digunakan untuk berbagai
kalangan baik masyarakat sekitar, wisatawan domestic maupun pemerintah setempat.
Peta interakktif wisata ini berisi tentang deskripsi, akses perjalanan, fasilitas dan
keterangan lain mengenai berbagai obyek – obyek wisata alam yang tersebar di
Kecamatan Maratua. Peta dapat di download secara online
melalui<http://www.mediafire.com/?g56le8364b314ci>atau
<http://maratuaisland.blogspot.com/2012/10/peta-interaktif-maratua.html>
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
127
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum objek – objek di Kabupaten Manggarai Barat dibagi menjadi tiga jenis,
antaralain :
1) WisataDanau
2) WisataGoa
3) WisataUnggulan
Berikut ini adalah Klasifikasi objek – objek wisata berdasarkan jenisnya.
Danau Haji Buang
Danau ini dinamakan sesuai dengan nama penemunya, yakni Haji Buang. Akses
menuju danau ini adalah menembus rimbunnya hutan dan kebun kelapa yang menjulang
tinggi dengan berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit. Selain berjalan kaki, akses
menuju danau ini juga dapat menggunakan perahu dari arah Lawang-lawang, Bohe
Bukut. Perjalanan yang dimulai dengan bukit berbatu yang sedikit menegangkan,
burung terbang dan hinggap di dahan pepohonan sekitar jalan setapak, kepiting kenari
yang bersembunyi di antara tumpukan batok kelapa akan semakin membuat anda
bertanya-tanya bahkan menunggu-nunggu keistimewaan danau ini. Selain
pemandangannya yang masih asri dan udara yang menyegarkan, danau Haji Buang juga
menyimpan kekayaan flora dan fauna dalam air. Tersedia perahu kecil bagi anda yang
ingin menikmati pemandangan di sekitar danau. Dari atas perahu anda akan melihat
puluhan ubur-ubur muncul ke permukaan, karena ubur-ubur yang terdapat di danau ini
tidak menyengat anda pun dapat leluasa menyentuh dan memegangnya. Tenangnya air,
rimbunnya pepohonan sekitar danau, dan
langit biru yang terbentang luas membuat anda
betah berlama-lama menikmati keindahan
danau Haji Buang, salah satu suguhan wisata
alam Maratua yang eksotis.
Gambar 7. Danau Haji Buang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
128
Danau Tana Bamban
Danau Tana Bamban merupakan salah satu
danau air payau yang ada di pulau maratua. danau
Tana Bamban mempunyai pemandangan yang
indah dengan air danau yang tenang, sehingga
sangat cocok untuk dikunjungi dengan dua spesies
ubur-ubur di dalamnya.
Gambar 8. Danau Tano Bamban
Goa sembat
Goa Sembat terletak di desa bohe silihan, kecamatan maratua. Goa ini termasuk
pada kawasan karst Maratua. Perjalanan menuju mulut goa dapat ditempuh dengan
berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit dengan jarak sekitar 2 km dari pusat desa.
Secara fisik, Letak mulut goa berada pada bagian sisi bukit dengan ukuran diameter goa
x m. kondisi sekitar goa masih alami dengan tutupan lahan berupa hutan lebat dan
semak belukar. Beberapa biota yang ada dalam goa yang dapat ditemukan berupa
kelelawar dan burung wallet.goa Sembat termasuk dalam tipe goa horizontal dan berair.
Gambar 9. Goa Sembat
Goa tangkapa
Goa tangkapa terletak pada perbatasan antara desa bohe silian dengan desa
payung-payung. Goa ini dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dan dilanjutkan
dengan berjalan kaki. Jarak tempuh perjalanan sekitar 15 menit dari pusat desa.Secara
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
129
fisik, letak mulut goa berada pada daerah cekungan. Kondisi sekitar goa masih sangat
alami dengan kondisi tutupan lahan berupa
hutan lebat dan semak belukar. Biota yang
ditemukan didalam goa berupa kelelawar,
wallet dan ambipigi.Goa tangkapa merupakan
goa horizontal dengan tipe crack (patahan)
sehingga dalam pengamatan dapat dijumpai
beberapa runtuhan batu dalam goa berupa batu
maupun boulder.
Gambar10 . Goa Tangkapa
Goa angkal-angkal
Terletak didesa payung-payung, kecamatan maratua. Lokasi goa sekitar 2 Km
dari pusat desa payung-payung. Goa ini dapat ditempuh dengan menggunakan
kendaraan bermotor dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Goa ini merupakan goa
horizontal yang memiliki lorong yang panjang dengan banyak cabang didalamnya.
Didalam goa ini memiliki banyak daya tarik wisata yang cukup tinggi , diantaranya
adalah adanya runtuhan atap goa pada bagian tengahnya sehingga ditengah perjalanan
penelusuran goa dapat terlihat sinar matahari yang masuk kedalam serta ornamentasi
yang terdapat didalamnya juga bervariasi yaitu stalaktit, stalaknit, sodastro,
microgordam, macrogordam, pilar, dll.
Gambar11 . Goa Angkal angkal
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
130
Goa penggunting
Terletak di desa payung-payung, kecamatan maratua. Lokasi goa sekitar 1 km
dari desa dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dengan menggunakan motor. Salah satu
keunikan dari goa ini merupakan tempat kepiting kenari bersarang. sehingga warga
sering masuk ke goa ini untuk berburu mencari kepiting kenari. Goa ini merupakan goa
horizontal yang hanya mempunyai lorong yang pendek namun didalamnya juga
mempunyai beberapa cabang. Salah satu cabang dari lorong goa penggunting
mempunyai ruangan yang cukup lebar. Di dalam lorong ini menyuguhkan keindahan
yang sangat menarik. Misalnya beberapa ornament goa seperti stalagtit, stalagmite,
pilar, maupun microgourdam dapat ditemukan pada ruangan ini. Sisi menarik yang lain
dari goa ini adalah dari kehidupan makhluk hidup dalam goa. Didalam goa kita dapat
menemukan beberapa spesies misalnya adalah laba-laba, ambipigi, lipan, jangkrik gua,
wallet, kepiting kenari, dan kelelawar. Beberapa dari spesies tersebut telah kehilangan
daya pengelihatannya karena lingkungan goa yang gelap. Sehingga ketika kita dekati
mereka tidak melakukan gerak refleks.
Gambar12 . Goa Penggunting
Goa Pogah
Terletak di desa bohe bukut kecamatan maratua. Jarak dari desa sekitar 2 Km
dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan berjalan
kaki. Waktu tempuh menuju goa ini sekitar 20 menit. Selama perjalanan kita disuguhi
pemandangan hutan maratua yang masih alami. Ditambah dengan beberapa formasi
batuan hasil dari proses tenaga endogen yaitu berupa pengangkatan. Sehingga ketika
diperjalanan kita dapat melihat bentukan batuan hasil dari proses patahan (crack). Goa
hapit merupakan goa vertikal yang secara proses terbentuk hasil dari runtuhan. sisi
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
131
menarik dari goa ini adalah mulut goa yang langsung menghadap ke dasar goa.
Sehingga ketika matahari bersinar, akan
tampak terlihat biasan sinar matahari masuk
ke dalam goa. Disamping itu, beberapa
ornamen goa seperti stalagtit, stalagmit,
flowstone, dan gorden tampak begitu indah.
Goa hapit merupakan goa berair dan bersifat
payau. Beberapa makhluk hidup yang
ditemukan adalah udang air payau, kelelawar,
dan walet.
Gambar13 . Goa Pogah
Goa hapit pogah
Terletak di desa bohe bukut, kecamatan maratua. Posisi mulut tidak jauh dari
goa pogah sekitar 100 meter. Goa ini merupakan goa vertikal dengan kedalaman sekitr
10 meter. Untuk memasuki goa ini diperlukan teknik khusus dan peralatan tersendiri
dalam menuruni goa tersebut. Daya tarik dari goa ini adalah ornamen goa yang cukup
indah seperti stalagtit, stalagmit, pilar, dan flowstone. Dasar goa ini berair dengan
ruangan yang cukup luas. Sehingga kita dapat berenang didalamnya. Di dalam gua ini
terdapat makhluk hidup yang ditemukan adalaah jangkrik, dan kelelawar.
Gambar1 . Goa Hapit Pogah
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
132
Tanjung Siku
Tanjung Siku merupakan pantai yang terdapat di utara desa Bohe Bukut. Karena
letaknya yang berada di ujung desa maka pantai ini biasa juga disebut pantai Ujung.
Nama Tanjung Siku diambil dari kondisi geografis tebing dan pantainya yang
membentuk seperti siku. Terdapat dua jalan yang
bisa digunakan dari dermaga Bohe Bukut menuju
pantai Tanjung Siku, yakni dengan cara menyusuri
pantai atau melewati jalan setapak di tengah kebun
kelapa penduduk setempat. Anda akan mendapati
pantai yang bersih dengan tebing yang di atasnya
terdapat tiga rawa kecil. Di dalam rawa kecil itulah
hidup spesies kecil udang merah.
Gambar15 . Pantai Tanjung Siku
Lawang-lawang
Dermaga lawang-lawang merupakan salah satu akses untuk masuk ke kampung
Bohe Bukut. Dermaga ini juga sering digunakan sebagai tempat pemberhentian kapal-
kapal warga. Pemandangan yang tampak dari dermaga ini ialah kampung Teluk Alulu,
Tanjung Bahaba, serta pulau-pulau kecil
di seberang pulau maratua seperti pulau
Panabahan, pulau Bakungan, pulau Abu-
abu, dan pulau Blingisan. Dermaga ini
merupakan jalur yang biasa digunakan
para nelayan untuk keluar masuk dari
perairan dalam.
Gambar16 . Dermaga Lawang lawang
Batu Payung
Batu karang besar ini terletak di tepi garis pantai di ujung kampung Payung-
payung, bagian atas batu yang menjorok ke arah laut membentuk payung membuatnya
terlihat unik. Karena batu inilah maka kampung ini disebut Payung-payung.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
133
Pemandangan di sekitar batu payung akan terlihat eksotis di saat matahari mulai
terbenam. Pasir putih yang lembut memanjakan
kaki, gerak-gerik lucu kerang klomang yang
berkejaran, ombak pantai dengan lembut menyapa,
jernihnya air mengajak anda untuk turut merasakan
kesegarannya, disaat mentari senja memantulkan
sinarnya di lautan lepas membuat diri terhanyut
dalam suasana tenang dan nyaman, sungguh senja
yang tak terlupakan.
Gambar17 . Batu Payung
Teluk Pea
Jika anda berjalan mengikuti jalan setapak selama kurang lebih 10 menit dari
arah batu Payung, maka anda akan menemukan garis pantai yang menjorok ke arah
daratan dan dipenuhi dengan tempurung kelapa, itulah Teluk Pea. Dalam bahasa bajau
pea berarti tempurung atau batok kelapa. Konon di teluk ini terdapat sebuah pabrik kecil
pengolah buah kelapa dan limbah tempurungnya bertumpuk di pantai teluk, karena
itulah ia dinamakan teluk Pea. Teluk Pea menjadi
obyek wisata kampung Payung-payung yang
kesekian bagi anda jika ingin menikmati keindahan
pantai dari sebuah teluk. Selain itu akan anda akan
menjumpai segerombolan penyu hijau yang akan
keluar masuk di Teluk Pea ini. Sehingga anda dapat
mengamati dengan bebas tingkah laku dari penyu
hijau.
Gambar18 . Teluk Pea
Dermaga Payung-payung
Dermaga yang masih aktif digunakan oleh masyarakat kampung Payung-payung
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
134
ini rupanya juga menjadi obyek wisata yang cukup menarik. Ketika berjalan memasuki
dermaga ini anda akan disambut dengan jernihnya air laut yang biru kehijauan, semakin
jauh berjalan anda akan melihat beberapa ekor penyu berenang dan mencari makan. Di
sekitar ujung dermaga anda akan dibuat kagum dengan terbentang luasnya terumbu
karang dan ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas. Ketika laut surut, pemandangan
pantai sekitar dermaga akan membuat anda terpancing untuk turut menyusuri pantai
menikmati keindahan terumbu karang yang memikat. Ketika laut pasang, anda bisa
berenang di sekitar dermaga bersama penyu-penyu dan ikan-ikan dengan berbagai
bentuk dengan warna-warni yang indah. Pemandangan lain yang tak kalah indahnya
adalah terbenamnya matahari. Telah
diakui oleh masyarakat setempat dan
wisatawan yang pernah berkunjung
bahwa pemandangan sunset terlihat
berbeda setiap harinya. Semilir angin
senja, langit yang berwarna merah saga,
merah jambu dan keungu-unguan
membuat anda berdecak kagum dan
terasa dimanjakan oleh alam Maratua.
Gambar19 . Dermaga Payung payung
KESIMPULAN
1) Setiap objek – objek wisata memiliki informasi spasial dan non spasial. Informasi
tersebut Kemudian digunakan untuk membangun sebuah Sistem Informasi
Geografis Kepariwisataan di Kecamatan Maratua
2) Pembuatan Sistem Informasi Geografis yang bertujuan untuk membantu para
wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata di Kecamatan Maratua
3) Pembuatan Sistem Informasi Geografis sangat didukung oleh masyarakat sekitar hal
ini dibuktikan dengan kerjasama masyarakat dan penulis dalam melakukan akuisisi
data di Kecamatan Maratua
DAFTAR PUSTAKA
Denny, C,danAgtrisari, I.,2003.Desain dan Aplikasi GIS, Geographic Information
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
135
System. . P.T. Gramedia: Jakarta.
Departemen, Kehutanan.,1993. Pedoman Analisis Daerah Operasi Obyek Wisata Alam.
Bogor.
Hadinoto, K., 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.UI-Press :
Jakarta.
Prahasta, E. 2005. Sistem Informasi Geografis. Edisi Revisi, Cetakan Kedua.
C.V.Informatika: Bandung.
Rosit Setiawan 2012, PEMANFAATAN GIS UNTUK INVENTARISASI DAN
PENGEMBANGAN DAERAH WISATA DIKABUPATEN MANGGARAI BARAT.
Jurusan Teknik Geodesi UGM : Yogyakarta
Senda, Albertus D. 2011. PEMANFAATAN GIS UNTUK INVENTARISASI DAN
PENGEMBANGAN DAERAH WISATA DIKABUPATEN MANGGARAI BARAT.
Jurusan Teknik Geomatika ITS : Surabaya .
Rigaux, P., 2002. Spatial Databases With Application to GIS. Morgan Kaufman : San
Francisco.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
137
NILAI FILOSOFI DALAM UPACARA ADATMAPPACCI PADA
PERNIKAHAN SUKU BUGISDI SULAWESI SELATAN
(Valueof Philosophy in Marriage Ceremony in Indigenous Mappacci Bugis Parts in South
Sulawesi)
Nasharuddin1, Wahyuddin
2, Irwanto
3& Abd. Rahman Rahim
3
1Pendidikan Fisika, Universitas Muhammadiyah Makassar
2Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Makassar
3Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar
ABSTRACT
Culture in Indonesia is a property that must continue to be preserved. Every
island in Indonesia has a story about the local culture itself. For example the Bugis
culture located in South Sulawesi province. Bugis tribe is a tribe that upholds the self-
esteem and dignity.The purpose of this study was to determine the socio- cultural
philosophy of values contained in the wedding ceremony mappacci Bugis community in
Bone regency. And benefits of this research is expected to add insight about the values
contained in the culture of the society in particular mappacci culture mappacci Bone so
it can be known what the true purpose. Mappacci traditional ceremony held at
„tudampenni‟, ahead of the marriage ceremony ceremony the next day.Mappacci
ceremony is one of the Bugis traditional ceremony in which the implementation using
henna leaves (Lawsania alba), or Pacci. Prior to this activity is usually done event
mappanré temme (khatam Al - Quran) and barazanji. Pacci leaf is associated with
paccing said that food is the cleanliness and purity.
Keywords: Bugis; Social and Cultural Value of Mappacci; Marriage
PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia kaya akan keanekaragaman suku, agama, dan bahasa yang
memungkinkan diadakannya penelitian bidang folklor. Folklor adalah cerita rakyat pada
masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang
beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
138
bangsa. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan
peristiwa sejarah. Pengetahuan dan penelitian folklor diperuntukkan sebagai
inventarisasi, dokumentasi, dan referensi.
Membahas kebudayaan yang ada di Indonesia, pasti tidak akan selesai karena
setiap pulau di Indonesia memiliki cerita kebudayaan tersendiri. Salah satunya
kebudayaan bugis yang terletak di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sistem nilai
budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam
masyarakat, mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai
apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini
menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang manifestasi
konkritnya terlihat dalam tata kelakuan. Sistem nilai budaya termasuk norma dan sikap
secara abstrak akan tercermin dalam cara berpikir dan secara konkrit terlihat dalam
bentuk pola perilaku anggota suatu masyarakat.
Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang
beribukota di Watampone (4o13-5
o06 LS dan 119
o42 -120
o40 BT). Bone menpunyai
gaya bahasa yang sangat khas, terkenal sangat halus di kalangan suku Bugis. Suku
Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini
sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau
martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat
malu keluarga, maka ia akan diusir atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di
zaman sekarang ini. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya
hanya karena tidak ingin menanggung malu dan tentunya melanggar hukum. Sedangkan
adat malu masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan. Walaupun tidak seketat
dulu, tapi setidaknya masih diingat dan dipatuhi.
Pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan
juga dapat mempererat hubungan antar keluarga suku. Menurut kebudayaan
Bugis,sebelum menikah ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh mempelai pria,
yaitu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali. Bila dia mampu memenuhi kebutuhan
sehari-hari maka dia boleh menikah.
Salah satu rangkaian kegiatan pernikahan suku bugis adalah upacara adat
mappacci yang harus dilakukan dengan penggunaan simbol-simbol yang sarat makna
filosofi. Di antaranya untuk menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kasih sayang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
139
dalam rumah tangga. Mappacci berasal dari kata “pacci”, yaitu daun yang dihaluskan
untuk penghias kuku, mirip bunyinya dengan kata “paccing” artinya bersih atau suci.
Melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya
memasuki bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis sekaligus merupakan malam
yang berisi doa.
Upacara adat mappacci dilaksanakan pada waktu tudampenni, menjelang acara
ijab kabul keesokan harinya. Upacara mappacci adalah salah satu upacara adat Bugis
yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (Lawsania Alba). Sebelum
kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan mappanré temme (khatam
Al-Quran) dan barazanji. Daun pacci ini dikaitkan dengan kata paccing yang
makananya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian, pelaksanaan mappacci
mengandung makna kebersihan raga dan kesucian jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang terkandung
dalam Budaya Upacara Adat Mappacci pada pernikahan adat masyarakat suku Bugis di
Kabupaten Bone, Sulawesi selatan.
MATERI DAN METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data
primer dan hasil studi literatur. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung
dan wawancara terhadap suku Bugis di Bone. Studi literatur menggunakan buku-buku
dan sumber bacaan yang relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
TataCara Pelaksanaan Mapacci
Sebelum mappacci dimulai, dilakukan padduppa (penjemputan) mempelai.
Protokol atau juru bicara keluarga mempersilakan calon mempelai menuju pelaminan
dengan mengucapkan:
Patarakkai mai bélo tudangeng
Naripatudang siapi siata
Taué silélé uttu patudangeng
Padattudang mappacci siléo-leo
Riwenni tudang mpenni kuaritu
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
140
Paccingi sia datu bélo tudangeng
Ripatajang mai bottinngngé
Naripattéru cokkong ri lamming lakko ulaweng
Para mempelai duduk berdekatan di sisi para pendamping. Mereka duduk
bersuka ria di malam tudampenni, mappacci pada sang raja atau ratu mempelai nan
rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahtakan
emas.
Orang-orang yang diminta untuk meletakkan pacci pada calon mempelai
biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya
kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon
mempelai di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci
di atas tangannya.
Jumlah orang yang meletakkan pacci ke tangan calon mempelai biasanya
disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai itu sendiri. Untuk golongan bangsawan
tertinggi jumlahnya 2x9 orang atau dalam istilah Bugis “duakkaséra”. Untuk golongan
bangsawan menengah sebanyak 2x7 orang atau “duappitu”. Sedangkan untuk golongan
di bawahnya bisa 1x9 atau 1x7 orang.
Adapun cara memberi pacci kepada calon mempelai adalah sebagai berikut:
1. Diambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan (telah dibentuk bulat supaya
praktis), lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama, ke
telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan do‟a
semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia. Kemudian kepada orang yang
telah memberikan pacci diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu
disuguhi sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena
sekarang ini sudah jarang orang yang memakan sirih, maka diganti dengan rokok.
2. Sekali-kali indo‟botting menghamburkan wenno kepada calon mempelai atau
mereka yang meletakkan daun pacar tadi dapat pula menghamburkan wenno yang
disertai dengan doa. Biasanya upacara mappacci didahului dengan pembacaan
barazanji sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada
Nabi Muhammad SAW atas nikmat islam. Setelah semua selesai meletakkan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
141
pacci ke telapak tangan calon mempelai, maka para tamu disuguhi kue-kue
tradisional yang diletakkan dalam bosara.
Makna Filosofi Simbol dalam Mappacci
1. Angkangulung (Bantal)
a) Bantal terbuat dari kapas dan kapuk, suatu perlambang “kemakmuran” dalam
bahasa bugis disebut “Asalewangeng”.
b) Bantal sebagai pengalas kepala, di mana kepala adalah bagian paling mulia bagi
manusia. Dengan demikian, bantal melambangkan kehormatan, kemuliaan atau
martabat. Dalam bahasa bugis disebut “Alebbireng”. Dengan demikian
diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan
saling menghormati.
2. Lipa‟ pitullampa (Sarung 7 lembar)
a) Sarung sebagai penutup tubuh. Tentunya kita akan merasa malu apabila tubuh
kita tidak tertutup. Dalam bahasa bugis disebut “Mabbelang/mallosulosu”.
Dengan demikian diartikan sebagai harga diri (merasa malu). Dalam bahasa
bugis disebut “Masiri/malongko” sehingga diharapkan agar calon mempelai
senantiasa menjaga harga dirinya. Dalam bahasa bugis “Sini nalitutuwi sirina”.
b) Sedang sebanyak 7 lembar tersebut, dalam bahasa bugis kata tujuh erat
kaitannya dengan kata patuju/tujui yang artinya benar, berguna, atau manfaat.
Sehingga diharapkan agar calon mempelai senantiasa berbuat, melakukan atau
mengerjakan sesuatu yang benar, berguna atau bermanfaat. Selalu benar.
Adapun bilangan 7 yang dalam bahasa bugis dikatakan “Pitu”, bermakna akan
jumlah atau banyaknya hari yang ada. Dimana tanggung jawab dan kewajiban
timbal balik antara suami dan istri harus dipenuhi setiap harinya.
3. Colli‟ daung utti (Pucuk daun pisang)
Daun pisang yang tua, belum kering, sudah muncul pula daun mudanya untuk
meneruskan kehidupannya dalam bahasa bugis disebut “Maccoli-maddaung”.
Melambangkan kehidupan sambung menyambung (berkesinambungan). Artinya
jangan berhenti berupaya, berusaha keras demi mendapatkan hasil yang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
142
diharapkan. Sebagaimana kehidupan pisang, nanti berhenti berpucuk setelah
sudah berubah.
4. Daun Panasa (Daun Nangka)
a) Kata “Panasa” mirip dengan kata “Menasa” yang berarti “Cita-cita luhur”
berlambang doa dan harapan mulia. Dalam bahasa Bugis disebut “Mammenasa
ri Decengnge” artinya senantiasa bercita-cita akan kebaikan atau kebajikan.
b) Bunga Nangka disebut “Lempu” dikaitkan dengan kata “Lempu” (dalam
bahasa Bugis) yang artinya kejujuran dan dipercaya. Sebagaimana salah satu
ungkapan atau syair Bugis, yakni : Duami Riala Sappo, Unganna Panasae,
Belona Kanukue artinya hanya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam
kehidupan dunia yang fana ini, yaitu Unganna Panasae (Lempu) yakni
kejujuran, dan Belo Kanuakue(Paccing) yang artinya kebersihan atau
kesucian. Dengan demikian diharapkan kiranya calon mempelai memiliki
kejujuran dan kesucian. Daun Nangka sebanya Sembilan lembar. Adapun arti
sembilan lembar yaitu semangat hidup atau kemenangan. Dalam bahasa Bugis
disebut Tepui Pennoi Atau Maggendingngi. Dalam arti kata rejekinya
melimpah ruah.
5. Wenno atau Benno (Jagung Melati/Beras Melati)
Yaitu jagung/beras yang digoreng/disangrai hingga mekar berkembang
dengan baik. Dalam bahasa Bugis disebut Penno Riale artinya mekar dengan
sendirinya. Sehingga diharapkan agar calon mempelai dapat mandiri dalam
membina rumah tangga.
6. Taibani/Patti (Lilin)
Taibani atau Patti berasal dari lebah yang dijadikan lilin sebagai suluh atau
pelita yang dapat menerangi kegelapan yang berarti panutan atau teladan.
Sehingga diharapkan calon mempelai dapat menjadi penerang, penuntun,
suritauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebah yaitu senantiasa hidup rukun,
tenteram, damai, rajin dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Selain
daripada itu lebah menghasilkan suatu obat yang sangat berguna bagi manusia
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
143
yaitu “Madu” dalam bahasa Bugis disebut “Cani‟ yang dikaitkan dengan kata
“Cenning” yang artinya manis. Sehingga diharapkan agar calon mempelai
senantiasa memiliki hati yang manis, sifat, perilaku dan tutur kata yang manis
untuk menjalin kebersamaan dan keharmonisan.
7. Pacci (Daun Pacar)
Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian.
Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci
hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya
sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar atau pacci yang
telah dihaluskan ini disimpan dalam wadah bekkeng sebagai permaknaan dari
kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan
masayarakat.
8. Capparu‟ Bekkeng (Tempat Pacci/Wadah yang terbuat dari Logam)
Antara Capparu‟ dan Pacci melambangkan dua insan yang menyatu dalam
suatu ikatan yang kokoh. Semoga pasangan suami isteri tetap menyatu, bersama
mereguk nikmatnya cinta dan kasih sayang yang sudah dijalin oleh dua rumpun
keluarga.
KESIMPULAN
Upacara adat mappacci adalah salah satu rangkaian acara dalam pernikahan
suku Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (Lawsania alba), atau
Pacci. Kegiatan ini dilakukan pada malam menjelang akad nikah keesokan harinya,
sebelum dilaksankan terlebih dahulu diadakan dengan mappenre temme (khatam Al-
Qur‟an) dan barazanji. Daun pacci ini dikaitkan dengan kata paccing yang maknanya
adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan mappacci mengandung
makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Selain itu semua perangkat dan kegiatan
dalam prosesi mappacci memiliki makna sosial yang dalam serta merupakan doa bagi
mempelai.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
144
DAFTAR PUSTAKA
Makkulau, Andi. 2008. Budaya Mappacci Masyarakat Sulawesi Selatan,
(http//www.tradisimappacci.com diakses tanggal 28 Mei 2013).
Muhtamar Syaff. 2004. Masa Depan Warisan luhur Kebudayaan Sulawesi
Selatan.Makassar: CV Adi perkasa
Najamuddin, Andi. 2010. Tata cara perkawinan adat Bone
(Online).(http://www.telukbone.blogspot.com diakses 25 November 2012)
Nurrofiq. 2010. Sejarah Berdirijnya Suku Bugis di Indonesia
(Online),http://www.Sejarah Berdirijnya Suku Bugis di Indonesia.htm (diakses 20
April 2012)
Palloge A, 1990. Sejarah Tanah Bone. Makassar: Yayasan Al-Muallim
Sanusi, Ahmad. 2001. Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi
Selatan.Makassar:Lamacca Press
Syaff, Muhtamar. 2004. Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan.
Makassar: CV Adi Perkasa
Uzey. 2009. Ilmu Budaya Dasar, Bahan Bacaan Pengajar. .
(http://www.pembagiannilai.com diakses 10 Juli 2013).
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
145
SRAWUNG : AN SEDULUR SIKEP ADVOCACY STRATEGY OF CHEMENT
FACTORY ESTABLISHMENT
Lutfi Untung Angga Laksana
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
ABSTRACT
This paper show conflict and advocacy stategy of publik policy in Sedulur Sikep‟s ways
of chement factory establishment in Sukolilo-Pati. This establishment initiated by
provincial goverment of Central Java and local goverment of Kabupaten Pati, also PT.
Semen Gresik as a capitalist. The purpose of this research are to know the conflict on
chement factory establishment process and explore local wisdom on Sedulur Sikep
Community wich is the transformation of srawung as an advocacy strategic of chement
factory establisment. This research used qualitative method with case study and content
analysis approachment. This research used enviromental ethics theory
(anthropocentrism, ecocentrism, and ecofeminism) and public policy advocacy theory.
The result of this reseacrh show that the conflict causes of two different prespectives,
interest-based prespeective and valu-based prespective. Goverment should admit and
accomodate Sedulur Sikep‟s rights so that the policy will be more aspirational and
democratic.
Keywords : Srawung, Sedulur Sikep. Conflict, Chement Factory Establishment
PENDAHULUAN
Kabupaten Pati yang terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan di bagian
timur Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi kawasan bentang alam karst atau lebih
dikenal dengan sebutan Pegunungan Kendeng Utara.Sumber daya alam yang dapat
ditemukan di Pegunungan Kendeng, salah satunya adalah batuan gamping dan sumber
daya air. Batuan gamping inilah yang menjadi primadona bagi perusahaan semen di
Indonesia, seperti PT. Semen Gresik1, PT. Indocement, dan PT. Holcim. Alasannya
1 Pada tahun 2012 PT. Semen Gresik berubah nama menjadi PT. Semen Indonesia
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
146
batuan gamping merupakan unsur utama dalam pembuatan semen, selain pasir besi dan
tanah liat. Selaian batuan gamping, Pegunungan Kendeng juga merupakan tandon air
raksasa bagi resapan air hujan dan mata air, walaupun tampak kering di atasnya.
Pegunungan Kendeng, khususnya di Kecamatan Sukolilo merupakan hunian
bagi masyarakat adat Sedulur Sikep, atau yang dahulu akrab ditelinga dengan sebutan
“suku samin”. Sejarah Sedulur Sikep/Samin sendiri telah dimulai pada masa kolonial
Belanda, tepatnya pada tahun 1890.
Permasalahan terjadi ketika pada tahun 2005 PT. Semen Gresik menawarkan
investasi modal sebesar Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
untuk mendiriakan pabrik semen baru di wilayah Jawa Tengah. Rencana pendirian
pabrik semen tersebut, secara administratif meliputi 4 kecamatan, yaitu Sukolilo,
Kayen, Gabus dan Margorejo, yang tarbagi dalam 14 desa dengan total luas kebutuhan
lahan 1.350 hektar. Lahan seluas 1.350 hektar tersebut nantinya akan digunakan oleh
PT. Semen Gresik sebagai lahan penambangan batu kapur (700 hektar), lahan
penambangan tanah liat (250 hektar), pabrik untuk produksi semen (85 hektar) dan
infrastruktur transportasi/jalan (85 hektar) serta penunjang kegiatan (230 hektar).2
Rencana pendirian pabrik semen tersebut bertentangan dengan kearifan lokal. Ini
berkaitan dengan keinginan masyarakat Sedulur Sikep agar yang ada selama ini ada
tidak berubah (keseimbangan ekologis, red) termasuk pola hidup sederhana yang sudah
turun-temurun terjaga. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, pabrik semen akan
menimbulkan dampak lingkungan yang mengancam kawasan Pegunungan Kendeng
yang selama ini menjadi sumber ekologi (air, gua, hewan, tanaman) serta kearifan lokal
masyarakat Sedulur Sikep dalam menjaga alam (dimanifestasikan sebagai kegiatan
bertani untuk merawat tanah, red). Tanah bagi masyarakat Sedulur Sikep merupakan
sumber kehidupan. Tanah adalah ibu yang memberi hidup dan memancarkan
kehidupan. Seperti dikatakan Vandana Shiva (dalam Keraf, 2010: 367), tanah bukan
sekedar rahim bagi reproduksi kehidupan biologis, melainkan juga reproduksi
kehidupan budaya dan spiritual.
Kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep yang hidup selaras dengan alam
(ekosentrisme), menjadi sumber utama resistensi penolakan rencana pendirian pabrik
2Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik di
Kabupaten Pati, Jawa Tengah 2008
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
147
semen di Sukolilo, Pati. Resistensi penolakan tersebut diwujudkan dengan kearifan
lokal masyarakat Sedulur Sikep yang khas yaitu dengan cara srawung.Srawungadalah
sebuah istilah Jawa yang mengandung arti kumpul atau pertemuan yang dilakukan lebih
dari satu orang atau kelompok. Menurut Gunretno, dalam srawung, masyarakat bisa
saling ngudoroso. Tidak hanya apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam
perasaan pun semua bisa diungkapkan. Srawung juga merupakan pengalaman-
pengalaman batin (esoterik) yang kadang sulit dibahasakan, tapi terasa di hati.3Dengan
adanya srawung semua permasalahan dalam realitas kehidupan mampu diselesaikan
secara bersama. Srawung dilakukan oleh masyarakat Sedulur Sikep sebagai kearifan
lokal untuk mencari solusi konstruktif dalam memecahkan suatu masalah yang sedang
dihadapi.
Srawung inilah yang kemudian menjadi strategi penolakan (advokasi kebijakan
publik, red) masyarakat Sedulur Sikep terhadap kebijakan rencana pendirian pabrik
semen di wilayah Sukolilo. Advokasi sendiri merupakan aksi strategis yang ditujukan
untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah
munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat (Socorro Reyes,Local
Legislative Advocacy Manual, Philippines: TheCenter for Legislative Development,
1997). Strategi advokasi yang dilakukan masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana
pendirian pabrik semen di wilayah Sukolilo sangat unik. Keunikan tersebut karena
aktivitas srawung yang dilakukan masyarakat Sedulur Sikep tidak disadari telah
mengalami transformasi4. Transformasi srawung diantaranya adalah pembentukan
organisasi lokal, menciptakan jaringan sosial, dan mengembangkan ruang publikatau
dalam masyarakat Sedulur Sikep ditandai dengan acara Wungon Rebo Pon.
MATERI DAN METODE
Prespektif penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif digunakan agar mendapatkan hasil analisis yang lebih dalam dan
detail.Sejalan dengan perspektif yang digunakan, maka untuk menjawab rumusan
masalah digunakan metode studi kasus dan analisis isi:Pertama, Studi kasus pada
intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau
3 Anononim. 2012. Srawung dalam Komunitas Sedulur Sikep. Diperoleh dari http://kabupatenpati.com/srawung-
dalam-komunitas-sedulur-sikep/ Pada 21 Mei 2012
4 Data diperoleh dari kompilasi hasil pra-penelitian lapangan pada September 2012
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
148
perorangan yang dijadikan unit analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif
(Yin, 2006).Kedua, berhubungan dengan fokus kajian merupakan peristiwa antar
waktu/time series, yaitu terjadi pada tahun 2005-2010, maka metode kedua yang
digunakan adalah metode analisis isi (content analysis).Analisis isi digunakan sebagai
“pisau” analisis untuk memahami polemik rencana pendirian pabrik semen yang
berlangsung dalam kurun waktu tahun 2005-2010 dan perjalanan perlawanan
masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana pendirian pabrik semen Sukolilo, Pati.
Dengan begitu, maka analisis isi dapat digunakan untuk merangkai peristiwa
berdasarkan antar waktu.
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data yang sifatnya
primer dan sekunder. Jenis data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh
secara langsung melalui wawancara secara mendalam.Wawancara mendalam dilakukan
dengan cara tanya jawab melalui tatap muka dengan key informan: 1) Gunretno sebagai
ketua Sedulur Sikep di Sukolilo yang berhubungan langsung dengan proses
transformasi srawung dan advokasi kebijakan publik, sekaligus sebagai ketua Jaringan
Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK); 2) Joko Santoso sebagai
Koordinator JM-PPK yang mengetahui banyak tentang perjalanan advokasi kebijakan
publik rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, Pati; 3) Mbah Rasno dan Mbah
Jarmin sebagai masyarakat kontra semen. Hal ini dilakukan untuk mendukung
pencarian jawaban atas rumusan permasalahan penelitian.
Data sekunder yang dimaksud adalah data atau informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber non wawancara, baik dari laporan riset, buku, majalah, koran, buletin,
internet, dan jurnal serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perspektif analisis
penelitian.Selain wawancara mendalam terhadap informan untuk mendapatkan data,
pengumpulan data juga dilakukan dalam bentuk studi dokumentasi.Data yang
dikumpulkan melalui dokumentasi adalah dokumen yang terkait dengan fokus
penelitian, baik dari laporan riset, buku, majalah, koran, buletin, internet, dan jurnal
serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perspektif analisis penelitian.
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
149
Pegunungan Kendengdi
Kabupaten Pati seluas
2.262,55 Ha, menyebar di tiga
kecamatan, yakni di wilayah
Sukolilo 1.682 Ha, Kayen
569,50 Ha, dan Tambakromo
11,05 Ha.
Lahirnya polemik rencana
pendirian pabrik semen
yang terjadi di Sukolilo, Pati
dalam kurun waktu tahun
2005-2010, akibat dari
adanya 2 (dua) cara
pandang yang berbeda
Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman
(dalam Moleong, 2002). Miles dan Huberman menawarkan teknik analisis yang lazim
disebut interactive model. Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan
(drawing conclusions).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Terjadinya Polemik Antara Pemerintah, Pemodal, dan Masyarakat
Kawasan Karst Sukolilo atau lebih dikenal sebagai Pegunungan Kendeng
Utara,merupakan “harta karun” bagi masyarakat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Pasalnya, dalam tubuh
Pegunungan Kendeng mengandung banyak sekali sumber
daya alam, seperti sumber daya air dan batuan gamping
akibat dari proses karstifikasi. Melihat “harta karun” yang
berlimpah, PT. Semen Gresik melirik Pegunungan Kendeng sebagai calon
pertambangan baru untuk bahan baku semen.
Rencana ini pula mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Berbeda dengan masyarakat Sedulur
Sikep, adanya pabrik semen akan mengacam
kelestarian lingkungan di Pegunungan
Kendeng.Perbedaan cara pandang itu lah yang
kemudian menjadi pemantik lahirnya kepentingan
dari pelbagai pihak.Akibatnya terjadi benturan
kepentingan yang melibatkan multiaktor, antara
pemerintah, pemodal, dan masyarakat. Dari benturan ini, maka nantinya akan lahir
polemik rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, Pati.
Pemetaan persepsi rencana pendirian pabrik semen dapat dijelaskan oleh konsep
Paul Wehr mengenai analisis pemetaan konflik. Menurut Paul Wehr (dalam Lambang
Trijono, 2006),analisis pemetaan konflik merupakan langkah awal untuk ikut campur
dalam mengelola suatu konflik.Berdasarkan pada faktor-faktor utama yang
memunculkannya, Paul Wehr mengatakan ada dua isu yang dapat dilihat sebagai isu
berbasis kepentingan (interest-based issue) dan isu berbasis nilai (values-based issue)
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
150
Masyarakat yang pro
semen setuju karena jika
adanya pabrik semen di
Sukolilo, maka akan
membuka kesempatan
kerja dan mengurangi
arus urbanisasi
(Paul Wehr dalam Lambang Trijono, 2006). Dengan melihat konsep Paul Wehr
tersebut, pembahasan pada bab ini nantinya akan difokuskuan pada kedua cara pandang
yang memicu terjadinya polemik rencana pendirian pabrik semen yang terjadi di
Sukolilo, Pati.
Pegunungan Kendeng Dilihat dari Cara Pandang Berbasis Kepentingan
(Interest-Based Issue). Pihak pertama adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, yang melihat peluang jika didirikan pabrik semen di
Sukolilo, maka hal tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari
penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak, nantinya pertumbuhan ekonomi akan
meningkat seiring dengan perkembangan pabrik yang didirikan. Dengan pertumbuhan
ekonomi yang pesat dan peningkatan pendapatan daerah, maka pembangunan sarana-
prasarana publik dan bidang lain di daerah Pati diharapkan juga akan meningkat.
Pertimbangan ini didasarkan dari best practice Kabupaten Tuban5, Jawa Timur yang
90% APBD berasal dari pajak pabrik semen.
Pihak kedua adalah pemilik modal atau PT. Semen Gresik. Sebagai perusahaan
semen terbesar di Indonesia, PT. Semen Gresik berkepentingan untuk semakin memacu
produksinya agar dominasinya di pasar semen nasional tetap terjaga dan meningkat.
Menurut analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat adanya indikasi praktek
persaingan usaha tidak sehat dalam industri semen.Persaingan tersebut terjadi antara
perusahaan semen dalam negeri seperti PT. Semen Gresik dengan perusahaan-
perusahaan lain yang sebagiannya merupakan milik asing seperti PT. Holcim dan PT.
Indocement Tunggal Perkasa (Tempo, 16 April 2009).
Pihak ketiga adalah masyarakat pro-tambang semen.
Menurut Bambang Susilo (Ketua Wakil Cabang Nahdatul
Ulama Sukolilo), adanya pabrik semen di Sukolilo menjadi
kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan baru dan lahan
pendapatan baru. Selain itu pendirian pabrik semen juga
berpotensi mengurangi arus urbanisasi yang selama ini terjadi di
5 Realitas kehadiran Semen Gresik di Tuban berdampak signifikan bagi peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD) setempat. Tingkat PAD Tuban saat pertama kali pabrik semen beroperasi di daerah itu
mencapai Rp 19.113.349.440 (1992/1993). Pada Tahun Anggaran 2010, PAD Tuban menyentuh angka
Rp. 106.369.268.224 (Suara Merdeka, 4 Agustus 2012)
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
151
Gunretno: Manusia tidak dapat
hidup tanpa dukungan dari alam,
tetapi alam tetap dapat menghidupi
dirinya sendiri, dan tidak
bergantung kepada manusia. Tanpa
bantuan manusia, alam dapat
menopang dirinya sendiri
Sukolilo.6 Pernyataan ini dikuatkan oleh Sutrisno warga Desa Kedumulyo ketua Forum
Masyarakat Peduli Pati Selatan (FMPPS), menurutnya pabrik semen akan menciptakan
kesempatan kerja, karena masih banyak pemuda yang mengganggur.Selain itu hasil
pertanian sudah tidak bisa digantungkan untuk kehidupann. Akibat banyaknya yang
menganggur, pemuda di desalebih memilih untuk merantau keluar daerah atau ke luar
negeri untuk mencari nafkah(Suara Merdeka, 2 Desember 2008).
Pegunungan Kendeng Dilihat Dari Cara Pandang Berbasis Nilai (Values-Based
Issue). Cara pandang berbasis nilai lahir dari etika ekosentrisme dan ekofeminisme.
masyarakat Sedulur Sikep dalam menjaga keseimbangan ekologi melalui bertani. Bagi
masyarakat Sedulur Sikep, hidup adalah bertani dan mencangkul, dan ajaran ini lah
yang turun-temurun diajarkan oleh sesepuh Sedulur Sikep hingga sekarang ini. Dengan
bertani, masyarakat Sedulur Sikep mengajarkan anak-anaknya atau turunnya untuk
hidup. Sawah bagi masyarakat Sedulur Sikep diinterprestasikan sebagai guru,
sedangkan cangkul sebagai alat tulisnya. Tidak hanya semata-mata bertani dan
mencangkul untuk memenuhi kebutuhan, melainkan upaya untuk merawat tanah.
Menurut Gunretno, dalam kesehariannya, masyarakat Sedulur Sikep selalu merawat
tanah dengan bertani. Tidak hanya menanam, masayarakat Sedulur Sikep juga merawat
tanah dengan baik. “Bertani itu berhubungan dengan (tanah) yang dipijak, merawat
(tanah) yang dipijak”, ungkap Gunretno (Suara Merdeka, 5 Agustus 2012).
Masyarakat Sedulur Sikep percaya, jika alam tidak seimbang, maka alam lah
yang akan menyeimbangkannya sendiri. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan alam,
bumi (tanah, red) harus dijaga dan dirawat, caranya adalah menjadi seorang petani.
Penolakan rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, bagi masyarakat Sedulur Sikep
adalah bagian dari menjaga keseimbangan
alam dengan “perbuatan”. Masyarakat
Sedulur Sikep mempunyai pemikiran,
manusia semakin lama semakin bertambah
dan tentu saja butuh bahan makanan.
Bahan makanan yang umum bagi orang Jawa adalah beras dari kegiatan pertanian.
Jikalau tidak ada petani dan tidak ada yang menanam beras lagi, maka kehidupan tidak
akan seimbang. Gunretno (Wawancara pada 6 Mei 2013) mengatakan semua yang
6Ibid... Mia. 2009. Jalan Terjal Eksploitasi Pati. Hlm. 6
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
152
Ukuran kesejahteraan bagi
masyarakat Sedulur Sikep
bukan karena memiliki
banyak harta dan benda,
namun kesejahteraan
adalah ketenangan
menjalani hidup
berada di alam sudah ada yang mengatur, di Jawa Timur dan Jawa Barat sudah menjadi
kawasan industri, seharusnya Jawa Tengah adalah titik penyeimbang, yaitu pertanian.
Selain itu, rencana pembangunan pabrik semen menyimpan resiko yang cukup
besarberupa kemunculan kerusakan lingkungan yang parah dan hilangnya
produktivitaspertanian di wilayah-wilayah sekitar Pegunungan Kendeng, terutama
KecamatanSukolilo dan Kecamatan Kayen. Apalagi sering terjadi bencana banjir dan
angin puting beliung di Sukolilokarena pegunungan Kendeng pada kurun waktu tahun
2005-2010(Wawancara dengan Gunretno pada 6 Mei 2013).Dampak lain yang ditakuti
masyarakat Sedulur Sikep adalah akan menimbulkan dampak sosial
masyarakat.“Dampak sosiale gede lo mas, antarane tonggo teparo dadi pecah belah,
pro-kontra koyok ngono kuwi yo dak ngrugeni, paseduluran sing maune rukun dadi ora
rukun. Disek sak durunge pabrik semen kan gak ono konflik sosial, dadi kudu
tanggungjawabe piye kuwi?, pabrike ora sido malah sak iki do neng-nengan”. Tambah
Gunretno (Wawancara pada 6 Mei 2013). (Dampak sosialnya besar mas, antara tetangga
dekat jadi pecah belah, pro-kontra itu ya merugikan, persaudaraan yang tadinya rukun
jadi tidak rukun. Dahulu sebelum adanya rencana pabrik semen kan tidak ada konflik
sosial, jadi tanggungjawabnya gimana?, pabriknya tidak jadi malah sekarang musuhan).
“Sak durunge PT. Semen Gresik mbangun pabrik semen, kuwi kudu iso jelaske
hakikat makmur, mergo kene ngroso nek sak iki kene wes makmur tanpo ono pabrik”,
ungkap Gunretno (Wawancara pada 6 Mei 2013). (Sebelum PT. Semen Gresik
membangun pabrik semen, mereka harus bisa menjelaskan dulu hakikat kesejahteraan,
karena kami merasa saat ini sudah sejahtera tanpa ada pabrik).
Ukuran kesejahteraan bagi masyarakat Sedulur Sikep adalah
Ketenangan. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, kesejahteraan
tidak bisa diukur dengan menggunakan uang saja. Masyarakat
Sedulur Sikep meyakini, kesejahteraan yang benar-benar
sejahtera adalah ketika manusia memperoleh ketenangan dalam hidup. “Kesejahteraan”
yang dijanjikan PT. Semen Gresik dalam pandangan masyarakat Sedulur Sikep tidak
sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari alam ketika dirawat (bertani, red).
Selain masyarakat Sedulur Sikep, sikap penolakan juga ditunjukkan oleh
masyarakat kontra semen.Masyarakat kontra semen sebagai informan selain masyarakat
Sedulur Sikep adalah warga dari Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Pati, yang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
153
bernama Mbah Rasno (80) dan Mbah Jarmin (75). Menurut pandangan Mbah Rasno,
jika pabrik semen jadi didirikan, maka akan mengancam hilangnya sumber daya air di
Pegunungan Kendeng.Ketakutan Mbah Rasno mengenai hilangnya sumber mata air
juga dirasakan oleh masyarakat Sedulur Sikep yang berada di Sukolilo.“Masalah semen
ngrugekno rakyat terkait sumber mata air, rakyat yo rugi, opo neh pertanian, mengko
nek ono semen mata air yo lenyap”, ujar Mbah Rasno (Wawancara pada 4 Mei 2013).
(masalah semen akan merugikan masyarakat terkait sumber mata air, masyarakat ya
rugi, apalagi pertanian, nanti kalau ada semen mata air akan lenyap).
Berbeda dengan Mbah Rasno, Mbah Jarmin menceritakan apa yang dahulunya
pernah diceritakan kakeknya mengenai pegunungan Kendeng. Atas dasar tersebut,
Mbah Jarmin menolak dengan tegas terhadap rencana pabrik semen. Menurut Mbah
Jarmin, cerita dari kakeknya jaman dahulu, pada masa penjajahan Belanda, Belanda
berencana akan membuat jalur rel kereta api. Jalur tersebut rencananya akan
menghubungkan Pati dengan Purwodadi7, dan akan menembus Pegunungan Kendeng
Utara. Dalam ceritanya Mbah Jarmin, untuk menembus Pegunungan Kendeng, Belanda
akan membuat trowongan yang nantinya akan menghubungkan Pati-Purwodadi.
Kemudian Belanda melakukan penginderaan jauh terhadap Pegunungan Kendeng,
hasilnya Belanda tidak berani dan membatalkan rencananya. Ketidakberanian Belanda
untuk membuat terowongan yang akan menghubungkan Pati-Purwodadi dengan alasan
di dalam perut Pegunungan Kendeng menyimpan kandungan sumber mata air yang
berlimpah ruah. Jika rencana tersebut jadi dilaksanakan, maka air tersebut akan keluar
terus menerus Pati-Purwodadi akan menjadi lautan.8
Dengan demikian dapat dikatakan, penolakan masyarakat Sedulur Sikep dan
masyarakat kontra semen terhadap rencana pendirian pabrik semen terjadi karena
beberapa faktor antara lain: Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan kawasan
karst di Pegunungan Kendeng; Hilangnya sumber mata air dan sungai bawah tanah
Pegunungan Kendeng untuk penghidupan dan kehidupan pertanian masyarakat;
Hilangnya habitat flora maupun fauna yang dilindungi; Pertanggungjawaban kepada
anak cucu ketika alam rusak; Potensi pemicu dampak sosial di masyarakat Sukolilo;
7 Purwodadi sekarang menjadi Kabupaten Grobogan 8Wawancara dengan mbah Jarmin pada 4 Mei 2013
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
154
Penurunan tingkat kesehatan masyarakat; dan Potensi bencana alam seperti banjir akan
menjadi lebih besar karena hilangnya fungsi penyerap air Pegunungan Kendeng.
Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Sedulur Sikep
Isu strategis yang diusung masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat kontra,
diantaranya adalah; Legitimasi yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kajian ilmiah; Adanya
kontroversi Amdal PT. Semen Gresik yang sarat dengan penyimpangan prosedural dan
klaim hasil kajian speleologi dan hidrogeologijauh dari kenyataan;Sosialisasi yang
dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, dan
PT. Semen Gresik sangat ekslusif tanpa melibatkan masyarakat kontra semen, sehingga
memicu timbulnya pro dan kontra;dan Kesewenangan Pemerintah dan PT. Semen
Grseik dalam aktivitas pembebasan lahan yang menimbulkan konflik horizontal dan
vertikal.
Pengambilan surat keputusan rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, Pati
tanpa adanya keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat Sukolilo yang
diproyeksikan akan terkena dampak. “Pengambilan keputusan izin pabrik semen di
Kabupaten Pati, masyarakat Kendeng tidak pernah diajak ikut berpartisipasi, diundang
pun tidak”, Joko (wawancara pada 2 Mei 2013). Selain itu, surat keputusan juga banyak
penyimpangan prosedural dan kelaikan. Sebagai contohnya adalah Surat Pernyataan
Bupati Pati No. 131/1814/2008 tentang Surat Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008
tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo yang sudah jelas melanggar
Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
Kebohongan yang ditunjukkan oleh PT. Semen Gresik adalahklaim kajian
speleologi dan hidrogeologi di dalam Amdal. Kebohongan inilah yang menjadi pemicu
lahirnya perlawanan di masyarakat Sedulur Sikep. Kajian speleologi mengklaim
menemukan 19 gua dengan dua kriteria yaitu berair dan tidak berair. Ada 8 gua yang
dinyatakan berair dan ada 11 gua yang dinyatakan tidak berair. Sementara untuk kajian
hidrogeolgi PT. Semen Gresik menemukan50 sumber mata air dan gua dengan aliran air
di dalamnya di dua Kecamatan, yaitu Sukolilo dan Kayen. Di Desa Sukolilo terdapat 19
mata air, Desa Gadudero terdapat 3 mata air, Desa Tompegunung terdapat 21 mata air,
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
155
Desa Kayen terdapat 4 mata air, Desa Kedumulyo terdapat 1 mata air, Desa
Sumbersuko terdapat 24 mata air. Di Kecamatan Sukolilo, sumber mata air memiliki
debit aliran bervariasi dari 1 liter/detik hingga 178,9 liter/detik. Mata air terbesar di
Kecamatan Sukolilo adalah Sumber Lawang yang terletak di dusun Tengahan dengan
debit aliran di musim kemarau mencapai 178,9 liter/detik.
Permasalahan pelik yang menjadi isu trategis advokasi masyarakat kontra
semen, khususnya masyarakat Sedulur Sikep salah satunya adalah kegagalan
pemerintah maupun pemodal dalam melakukan komunikasi publik. Mulai dari
Konsultasi publik rencana pendirian semen; Konsultasi KA-Amdal; Sosialisasi hasil
Amdal; dan Sosialisasipendirian pabrik semen. Dari kegagalan inilah maka timbul 2
kutub di masyarakat Sukolilo, yaitu masyarakat pro semen dan masyarakat kontra
semen. Waktu masih dalam tahapan KA Amdal ada banyak sekali kritikan yang
dilontarkan, khususnya JM-PPK, sehingga kesepakatannya harus ada pembenahan.
Akan tetapi, kenyataan berkata lain, KA Amdal yang belum dibenahi tiba-tiba Amdal
sudah jadi dan akan dipresentasikan pada tanggal 1 Desember 2008.9“Opo meneh
sosialisasi KA Amdal sing ditindaki pabrik semen karo pemerintahmung kanggo pantes-
pantesan formalitas. Nanging nek sosialisasi secara utuh biso dipahami pihak
masyarakat opo ora kan perlu bukti”, ungkap Gunretno (wawancara pada 6 Mei 2013).
Setelah PT. Semen Gresik mendapatkan „doa restu‟ dari Pemerintah Kabupaten
Daerah Pati melalui Keputusan Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten
Pati Nomor: 591/001/2008 tentang Izin Lokasi Eksploitasi Daerah Pati, selanjutnya
melakukan pembebasan lahan10
. Dalam pembebasan lahan inilah Pemerintah dan PT.
Semen Gresik ditengarai melakukan intimidasi dan kesewenangan hingga memunculkan
konflik horizontal dan vertikal. Contoh kesewenangan yang nyata adalah tanpa adanya
kesepakatan, PT. Semen Gresik, dibantu perangkat desa dan masyarakat pro semen
memasang patok di tanah-tanah warga di Dusun Curug, Desa Kedumulyo, Kecamatan
Sukolilo yang diproyeksikan untuk penambangan bahan baku semen.
Dalam membangun opini dan fakta sebagai pendukung advokasi yang berbasis
bukti, masyarakat Sedulur Sikep melakukan beberapa hal, diantaranya; Opini yang
dibangun masyarakat Sedulur Sikep adalah melakukan srawung ke 14 Desa yang
9 Wawancara dengan Joko Sanoto pada 2 Mei 2013 10 PT. Semen Gresik mematok harga beli Rp. 7.000/m2 untuk tanah darat dan Rp. 13.500/m2 untuk tegalan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
156
diproyeksikan menjadi calon lokasi berdirinya pabrik semen (terkait isu strategis);
Mendirikan posko lingkungan untuk memberikan informasi mengenai kemanfaatan
Pegunungan Kendeng; dan Mengikuti/menyelenggarakan diskusi dan seminar publik
terkait rencana pendirian pabrik semen. Sedangkan faktanya, masyarakat Sedulur Sikep
mengadakan studi banding ke Tuban, Jawa Timur untuk mengungkapkan fakta di
lapangan dan Bekerja sama dengan berbagai akademisi, organisasi lingkungan, dan
LSM untuk membuktikan klaim hasil kajian speleologi dan hidrogeologi Amdal PT.
Semen Gresik.
Dalam mengumpulkan fakta, masyarakat Sedulur Sikep mematahkan klaim
Amdal PT. Semen Grseik yang dibuat oleh PPLH Undip. Pada kenyataannya, kajian
speleologi dan hidrogeologi hasil PPLH Undip berbeda jauh dengan hasil kajian
masyarakat Sedulur Sikep. Hasil Amdal yang dilakukan oleh PPLH Undip menemukan
19 gua dengan dua kriteria yaitu berair dan tidak berair. Ada 8 gua yang dinyatakan
berair dan ada 11 gua dinyatakan tidak berair, sedangkan dari penelusuran yang
dilakukan oleh Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta dan
Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta beserta Jaringan Masyarakat
Peduli Pegunungan Kendeng dan masyarakat Sedulur Sikep, menemukan 24 gua yaitu
16 gua dinyatakan berair, 4 gua dinyatakan tidak berair, dan 4 tidak ada keterangan.
Untuk penelusuran sumber mata air, PPLH Undip menemukan50 sumber mata
air dan gua dengan aliran air di dalamnya di dua Kecamatan, yaitu Sukolilo dan Kayen.
Sedangkan tim Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta dan
Acintyacunyata Speleological Club (ASC) Yogyakarta beserta Jaringan Masyarakat
Peduli Pegunungan Kendeng dan masyarakat Sedulur Sikep menemukan lebih dari 50
mata air yaitu 79 sumber mata air yang mengelilingi Kawasan Karst Sukolilo Pati
(Kendeng utara) di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Kayen. Perbandingannya
adalah 19 gua berbanding 24 gua dan 50 sumber mata air berbanding 79 sumber mata
air.
Sebagai masyarakat adat, tentunya masyarakat Sedulur Sikep mempunyai
standar sendiri dalam memahami sistem kebijakan, standar yang dipakai dalam
memahami rencana pendirian pabrik semen adalah dengan falsafah kejujuran. Banyak
legitimasi yang dikeluarkan adalah hasil dari ketidakjujuran pemerintah, karena tanpa
adanya musyawarah dengan masyarakat yang diproyeksikan menjadi “korban” rencana
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
157
pendirian pabrik semen, sebagai contohnya adalah pada Surat Pernyataan Bupati Pati
No. 131/1814/2008 tentang Surat Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang
Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo, kawasan yang semula pertanian dan
pariwisata dialihfungsikan sebagai kawasan pertambangan dan industri.
Berikut adalah tabel dan penjelasan mengenai kontradiksi legitimasi rencana
pendirian pabrik semen PT. Semen Gresik dengan peraturan pemerintah maupun hasil
kajian ilmiah:
Kontradiksi Legitimasi Rencana Pendirian Pabrik Semen
Peraturan Rencana Pendirian Pabrik
Semen Bertentangan dengan
Surat Pernyataan Bupati Pati No.
131/1814/2008 tentang Surat
Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Peraturan Pemerintah nomor
26 tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
Kearifan
Lokal M
asyarak
at Sed
ulu
r Sik
ep
Undan
g-U
nd
ang D
asar Neg
ara Rep
ublik
Indonesia T
ahun 1
945, P
asal 18 B
ayat (2
)
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun
2008 tentang RTRW 2008-2027
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
Nomor 591/058/2008 tentang Ijin
Lokasi eksploitasi daerah Pati;
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi
Penambangan Batu Kapur;
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
Nomor 541/052/2008 tentang Lokasi
Penambangan Tanah Liat;
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
158
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 128 Tahun 2008 tentang
Penetapan Kawasan Karst Lindung
Sukolilo;
Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
Nomor:1456.K/20/MEM/200
0 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Kars
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral
Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor: 660.1/27/2008 Tentang
Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Hidup Pembangunan Pabrik Semen PT.
Semen Gresikdi Kabupaten Pati.
Kajian Pusat Studi
Manajemen Bencana UPN
“Veteran” Yogyakarta beserta
Acintyacunyata Speleological
Club (ASC) Yogyakarta,
mengenai Pegunungan
Kendeng Utara
Sumber: Hasil analisis temuan di lapangan
Alasan mengapa bertentangan, dikarenakan legitimasi rencana pendirian pabrik
semen di Sukolilo, Pati berkontradiksi terhadap: Kearifan lokal masyarakat Sedulur
Sikep tentang etika lingkungan yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2) menyatakan, “Negara mengakui
dan menghormatikesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adat besertahak-hak
tradisionalnya sepanjangmasih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakatdan
prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia”. Dalam pasal tersebut mempunyai
makna, seharusnya pemerintah mengakui dan menghormati masyarakat adat yang masih
memegang teguh pada kearifan lokalnya. Implikasinya, masyarakat adat memperoleh
hak atas sumber daya alam.
Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sangat
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional. Alasannya, ada perubahan fungsi lahan dan tata ruang yang
semestinya difungsikan sebagai pertanian dan pariwisata dirubah menjadi industri dan
pertambangan. Pengalihfungsian tersebut tepatnya di Pegunungan Kendeng, sehingga
kontradiktif dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tahun 2008. Berikut
penjelasannya; Pasal 51 huruf (e) Salah satu kawasan lindung nasional adalah Kawasan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
159
Lindung Geologi→ Pasal 52 ayat (5) Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: (a)
Kawasan cagar alam geologi; (b) Kawasan rawan bencana alam geologi; (c) Kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap air tanah→ Pasal 53 angka (1) Kawasan cagar
alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a)
Kawasan keunikan batuan dan fosil; (b) Kawasan keunikan bentang alam; (c) Kawasan
keunikan proses geologi→ Pasal 60 ayat (2) huruf (f) Kawasan cagar alam geologi
sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (5) huruf (a) ditetapkan dengan kriteria
Memiliki Bentang Alam Karst.
Berdasarkan kajian Pegunungan Kendeng Utara yang dilakukan oleh Pusat Studi
Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta dan Acintyacunyata Speleological
Club (ASC) Yogyakarta, hasilnya menyimpulkan Pegunungan Kendeng Utara adalah
Kawasan Karst Kelas I. Jika melihatKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pasal 12 dan pasal 14, tentunya Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Karst
Lindung Sukolilo dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/27/2008
Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Semen PT.
Semen Gresikdi Kabupaten Pati menyalahi aturan.
Pembangunan koalisi dilakukan masyarakat Sedulur Sikep dengan cara kearifan
lokalnya yang khas yaitu dengan transformasi srawung. Bentuk dari transformasi
srawung tersebut adalah organisasi lokal, jaringan sosial, dan Wungon Rebo Pon/Ruang
Publik. Melalui organisasi lokal yang dibentuk, SPP, FMPL, JM-PPK dan KPPL
Simber Wareh, masyarakat Sedulur Sikep mampu mengorganisir seluruh kalangan
masyarakat yang berada di wilayah Pegunungan Kendeng, kususnya Kecamatan
Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo untuk memperkuat basis gerakan dan mempunyai
bargaining posisition yang kuat. Tidak hanya itu, untuk menguatkan advokasi kebijakan
publik berbasis data, masyarakat Sedulur Sikep mampu menciptakan jaringan sosial dari
pelbagai kalangan. Jaringan yang tercipta tidak hanya masyarakat yang kontra semen
saja, akan tetapi meliputi Budayawan, Seniman, Akademisi, Birokrat, Politisi Lokal,
Kelompok Aliran Agama, dan LSM. Sementara untuk memperkuat ikatan esoterik dan
menyadarkan masyarakat, masyarakat Sedulur Sikep mengadakan wungon rebo
pon/ruang publiksebagai media untuk srawung. Kesadaran yang ingin dibangkitkan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
160
dalam acara wungon rebo pon adalah kesadaran mengenai masyarakat akan
kemanfaatan Pegunungan Kendeng dalam kehidupan ekologis dan dampak
keterancaman lingkungan.
Dalam merancang sasaran dan strategi, masyarakat Sedulur Sikep sudah
merencanakan dengan matang. Sasaran advokasi yang akan dituju adalah Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, PT. Semen Gresik.
Sementara strategi aksi demo dan kampanye dengan Press Releases; Melakukan Lobby
dan Negosiasi; dan mengajukan Legal StandingUntuk mengimplementasikan strategi
advokasi kebijakan publik, masyarakat Sedulur Sikep melakukan banyak cara antara
lain: Melakukan Aksi Demo dan Kampanye penolakan rencana pendirian pabrik semen
dengan Press Release sebagai dasar penolakan rencana pendirian pabrik semen; dan
Melakukan Lobby dan Negosiasi terhadap pemangku kebijakan dari Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati; Legal Standing terhadap
Keputusan Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor
540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur dan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Karst Lindung Sukolilo.
Kemenangan yang diraih masyarakat kontra semen yang berada di wilayah
Pegunungan Kendeng, terutama masyarakat Sedulur Sikep adalah perjuangan panjang
dan berliku.Upaya legal standing yang dilakukan masyarakat Sedulur Sikep dengan
bantuan dari Walhi Jawa Tengah dan BLH Semarang mau tidak mau harus keluar
masuk persidangan. Persidangan pertama yang dilakukan di PTUN Semarang, gugatan
Walhi dikabulkan sepenuhnya, implikasinya Keputusan Kepala Kantor
PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi
Penambangan Batu Kapur dicabut. Tidak berhenti disitu saja, upaya banding yang
dilakukan oleh pihak PT. Semen Gresik atas putusan PTUN Semarang, juga dikabulkan
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Tanpa henti masyarakat
Sedulur Sikep dan Walhi melakukan perlawanan, hingga pada akhirnya kasasi yang
diajukan Walhi kepada Mahkamah Agung (MA) dikabulkan.
Dalam Putusan MA yang menyebutkan daerah kawasan karst, yaituKawasan
Perbukitan Batu Gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo,Kecamatan Kayen,
Kecamatan Tambakromo, di Kabupaten Pati danKecamatan Brati, Kecamatan
Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, KecamatanWirosari, Kecamatan Ngaringan di
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
161
Kabupaten Grobogan sertaKecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa
Tengah sebagaikawasan kars Sukolilo. Evaluasi yang dilakukan pada akhirnya adalah
dicabutnya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati
Nomor 540/052/2008 tentang Lokasi Penambangan Batu Kapur di PTUN Semarang
pada 6 Agustus 2012 dan pencabutan ini diperkuat oleh keputusan kasasi Mahkamah
Agung (MA) pada 27 Mei 2010. Dengan dicabutnya surat izin PT. Semen Gresik, maka
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor
591/058/2008 tentang Izin Lokasi eksploitasi daerah Pati dan Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor 541/052/2008 tentang Lokasi
Penambangan Tanah Liat juga ikut tercabut.
KESIMPULAN
Kemenangan yang diraih masyarakat kontra semen terhadap PT. Semen Gresik,
tidak terlepas dari peran penting masyarakat Sedulur Sikep dalam menyuarakan
penolakannya. Penolakan yang didasari atas kearifan lokal terhadap lingkungan, telah
melahirkan suatu pergerakan perjuangan melawan keterancaman lingkungan. Ajaran
hidup sebagai petani telah memberikan kesadaran kepada masyarakat Sedulur Sikep
untuk bersahabat dengan alam. Keintiman dengan alam inilah yang mendasari eratnya
hubungan masyarakat Sedulur Sikep dengan lingkungan, khususnya Pegunungan
Kendeng. Dengan begitu, maka rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pati bekerja
sama dengan PT. Semen Gresik yang akan membangun pabrik semen baru di Sukolilo
dipahami masyarakat Sedulur Sikep akan merusak alam dan lingkungan.
Pada dasarnya polemik yang terjadi atas rencana pendirian pabrik semen di
Sukolilo, Pati merupakan pertarungan 2 perspektif. Pihak pertamayang mengusung
perspektif berbasis kepentingan (interest-based issue)adalah Pemerintah (Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati), swasta (PT. Semen Gresik), dan
masyarakat Sukolilo pro-tambang semen. pemerintah berpandangan potensi sumber
daya alam yang melimpah seharusnya didayagunakan untuk tujuan meningkatkan
kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat pro semen, adanya pabrik semen
di Pati, maka akan mengurangi arus urbanisasi dan dapat menciptakan kesempatan kerja
bagi masyarakat Sukolilo pada khususnya. Sementara bagi pemodal, berkepentingan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
162
untuk semakin memacu produksinya agar dominasinya di pasar semen nasional tetap
terjaga. Aktor
Berbanding 180o
dengan pihak kedua yang menggunakan perspektif berbasis
nilai (values-based issue) yaitu masyarakat yang kontra terhadap rencana pendirian
pabrik semen. Pihak yang terdiri dari masyarakat Sedulur Sikep, dan masyarakat kontra
yang tergabung dalam JM-PPK dan KPPLSimbar Wareh memiliki cara pandang lain.
Adanya pabrik semen akan mengganggu keseimbangan alam, terutama sumber mata air
yang digunakan masyarakat sehari-hari untuk penghidupan dan kehidupan. Selain itu,
resiko yang ditimbulkan dari adanya pabrik semen adalah kekhawatiran terhadap resiko
dampak sosial di masyarakat.
Melihat polemik yang terus berkepanjangan dan kenyataan keterancaman
lingkungan, terutama sumber daya air dan eksistensi masyarakat Sedulur Sikep yang
notabene sebagai petani, para tokoh Sedulur Sikep berinisiatif menyadarkan masyarakat
di sekitar Pegunungan Kendeng. Melalui kearifan lokal, masyarakat Sedulur Sikep
melakukan srawung dari satu rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kecamatan ke
kecamatan, hingga dari kabupaten ke kabupaten. Dalam srawung tersebut, masyarakat
Sedulur Sikep menjelaskan kepada warga akan kemanfaatan Pegunungan Kendeng dan
ancaman lingkungan jika pabrik semen berdiri di Pegunungan Kendeng.
Transformasi srawung inilah yang kemudian menjadi strategi advokasi
kebijakan publik masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana pendirian pabrik semen di
Sukolilo, Pati. Konsep advokasi kebijakan publik Socorro Reyes,Local Legislative
Advocacy Manual, Philippines: TheCenter for Legislative Development,
(1997)sepenuhnya bisa menjelaskan kasus pada penelitian ini. Secara ideal tujuan dari
kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi
yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Advokasi kebijakan publik
yang dilakukan oleh masyarakat Sedulur Sikep merupakan upaya untukmenciptakan
kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah munculnya kebijakan
yang merugikan bagi masyarakat. Konsep kerangka kerja advokasi kebijakan publik,
sangat relevan dengan penemuan kasus yang terjadi di lapangan.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
163
DAFTAR PUSTAKA
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Pabrik Semen
PT. Semen Gresik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah 2008.
Anonim. 2008. Kelompok Pro Pabrik Semen Kerahkan Masa. Suara Merdeka, 2
Desember 2008. Diperoleh dari
<http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2008/12/02/41706/Kel
ompok-Pro-Pabrik-Semen-Kerahka n-Massa Pada 20 Juni 2013>
Anonim. 2012. Srawung dalam Komunitas Sedulur Sikep. Diperoleh dari
http://kabupatenpati.com/srawung-dalam-komunitas-sedulur-sikep/ Pada 21 Mei
2012
Callicot, J. Baird dan Robert Frodeman. 2010.Encyclopedia of Enviromental Ethics and
Philosophy. New York: Gale Encage Learning.
Kelana, Setiawan Hendra. 2012. Belajar dari Kegagalan di Pati, Perkuat Program
Pantau Lingkungan. Suara Merdeka, 4 Agustus 2012. Diperoleh dari
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2012/08/04/945/Belajar
-dari-Kegagalan-di-PatiPerkuat-Program-Pantau-Lingkungan pada 23 Juni
2013>
Keraf, Sonny. 2010. Etika Lingkungan hidup. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Kompilasi slide presentasi kuliah Advokasi Kebijakan Publik oleh Ambar
Widaningrum/Budi Wahyuni, FISIPOL UGM.
Moleong, lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
Suyami. 2007. Kearifan lokal di lingkungan masyarakat samin kabupaten blora, jawa
tengah. Yogyakarta: kantor pariwisata dan kebudayaan kabupaten blora.
Diperoleh dari Website resmi Pemkab blora, Sejarah Samin,
http://www.blorakab.go.id/03samin.php Pada Pada 21 Mei 2012
Tobing, Sorta. 2009. “Tiga Produsen Semen Diduga Lakukan Monopoli”. Tempo, 16
April 2009. Diperoleh dari http://www.tempo.co/read/news/2009/04
/16/090170705/Tiga-Produsen-Semen-Diduga-Lakukan-Monopoli diakses pada
28 April 2013.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
164
Trijono, Lambang. 2002. Pemetaan dan Penjelasan Konflik. Makalah Disajikan pada
Workshop Konsolidasi Jaringan dan Pemetaan Potensi Konflik di Yogyakarta-
Jateng, Lembaga Lintas Sara Yogyakarta. Yogyakarta.
Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta:Raja Grafindo Persada .
Susanto, Gunawan Budi. 2012. Gunretno: Pada Tanah Pun Kita harus Jujur. Suara
Merdeka, 5 Agustus 2012. Diperoleh dari epaper.suaramerdeka.com/..
./02EM05H12MGU.pdf
Wibisono, Sony. 2008. Menolak sebagai Bentuk Peduli Lingkungan. Suara Merdeka, 26
April 2008. Diperoleh dari
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/04/26/1096
9/Menolak-sebagai-Bentuk-Peduli-Lingkungan
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
165
INDONESIA CAPITAL MARKET REACTION TO THE OIL PRICE
INCREASE POLICY 22 JUNE 2013
(Event study on LQ-45 Index, manufacturing sector, and mining sector)
Ali Sulas Hidayat
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT
This research was event study with the objectives to investigate whether fuel price
increase policy announced by Indonesian government contain any informational value
to Indonesian Stock Exchange (IDX). The reaction was determined by the occurrence of
Average Abnormal Return which is different to zero during event period.This research
was using samples of 37 Index LQ-45 companies list, 98 manufacturing companies, and
30 mining companies. The samples selection method is purposive sampling. Data used
in this research was daily price of shares on closing and market index (IHSG and LQ-
45). Observation period was divided in to two periods, estimation period 100 days and
event period 21 days (10 days before, 1 day event date, 10 days after).The result of this
research indicate that abnormal return received by investor is significant in the days
surrounding the event date for LQ-45, manufacturing sector, and mining sector. This
result mean that the fuel price increase announcement possess important information to
the stock market which lead changes in the stock price of Index LQ-45, manufacturing
sector, and mining sector. The result of paired sample t-test show that Average
Abnormal Return before and after the event not significantly different for Index LQ-45,
manufacturing sector, and mining sector.
Keywords: Event study, Abnormal return, Fuel Price Increase Policy
PENDAHULUAN
Pasar modal di Indonesia dalam perkembangannya telah menunjukkan sebagai
bagian dari instrumen perekonomian yang memiliki peran cukup penting. Komitmen
pemerintah Indonesia terhadap peran Pasar Modal tercermin di dalam Undang-Undang
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
166
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana dinyatakan
bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional,
sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi
masyarakat. Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak bisa lepas dari
berbagai pengaruh lingkungan di sekitarnya, baik berupa kebijakan pemerintah,
peristiwa perekonomian atau politik, kerusuhan sosial, bencana alam, dan lain
sebagainya.
Demikian pula kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM), pada akhirnya juga akan mempengaruhi pasar modal. Hal ini
dikarenakan bahan bakar minyak memiliki peranan yang sangat penting sebagai bahan
bakar untuk menggerakkan perekonomian. Pasokan minyak bumi merupakan input
penting dalam proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik,
menjalankan mesin produksi, dan mengangkut bahan baku atau mengirim hasil produksi
ke pasar.
Perubahan harga BBM akan berdampak pada perubahan-perubahan biaya
operasional perusahaan. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berimbas pada
tuntutan karyawan untuk menaikkan upah. Di sisi lain, kenaikan harga BBM akan
menurunkan daya beli masyarakat. Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya
biaya produksi dan turunnya daya beli masyarakat berarti memperlemah perputaran
roda ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini dapat mempengaruhi iklim investasi baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar
modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman (Jogiyanto, 2010). Metode studi peristiwa sudah banyak digunakan dalam
penelitian untuk menguji reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, baik peristiwa ekonomi
yang berkaitan langsung dengan emiten atau peristiwa non-ekonomi (misalnya peristiwa
politik, kerusuhan sosial, atau kebijakan pemerintah).
Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information
content) dari suatu peristiwa dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar
bentuk setengah kuat(Jogiyanto, 2010). Pengujian kandungan informasi dimaksudkan
untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman tersebut mengandung
informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
167
diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari
sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai
nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Pengumuman yang
mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar.
Sebaliknya, pengumuman yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan
abnormal return kepada pasar.
Karena kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) merupakan isu penting dan dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian secara
nasional, maka penelitian mengenai pengaruh kebijakan tersebut perlu dilakukan.
Penelitian ini menguji kandungan informasi dari peristiwa kenaikan harga BBM tanggal
22 Juni 2013 dengan melihat reaksi pasar modal terhadap peristiwa tersebut. Pendekatan
yang digunakan adalah event study dengan mengamati abnormal return untuk
mengukur reaksi tersebut.
Penelitian ini menggunakan sampel saham Indeks LQ-45 untuk melihat reaksi
pasar secara keseluruhan. Selain menggunakan Indeks LQ-45, penelitian ini juga
menggunakan saham sektor manufaktur dan saham sektor pertambangan. Alasan
peneliti menggunakan sampel saham sektor manufaktur karena aktivitas sektor ini
berkaitan erat bahan bakar minyak, mulai dari pembelian bahan baku, proses
pengolahan bahan, hingga distribusi atau penjualan produk. Proses produksi tersebut
sangat terpengaruh oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Alasan peneliti
menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan adalah karena kenaikan harga
BBM tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga
minyak dunia ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi harga komoditas-komoditas
energi dan pertambangan.
Masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah peristiwa kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 menghasilkan
abnormal return pada saham Indeks LQ-45, saham sektor manufaktur, dan saham
sektor pertambangan?
2. Apakahrata-rata abnormal return selama 10 hari sebelum peristiwa berbeda dengan
rata-rata abnormal return selama 10 hari setelah peristiwa kenaikan BBM tanggal
22 Juni 2013 pada saham Indeks LQ-45, saham sektor manufaktur, dan saham
sektor pertambangan?
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
168
MATERI DAN METODE
Identifikasi Peristiwa
Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai perubahan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2013. Undang-undang tersebut menjadi dasar pemerintah untuk
menaikkan harga BBM. Namun setelah usulan kenaikan BBM di setujui oleh DPR pada
tanggal 17 Juni, pemerintah tidak langsung memberlakukan kenaikan harga BBM
tersebut. Penundaan pemberlakuan kenaikan harga BBM ini membuat pasar modal
mengalami kondisi ketidakpastian dan kepanikan. Pada tanggal 21 Juni 2013 pukul
23:00 WIB, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
mengumumkan berita resmi mengenai pemberlakuan harga BBM yang baru.
Dalam penelitian ini tanggal 24 Juni 2013 dipilih sebagai event date (t0).
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 21 Juni 2013, dan secara
resmi mulai memberlakukan harga baru tersebut pada tanggal 22 Juni 2013. Karena
tanggal 22 Juni 2013 adalah hari Sabtu dan pasar saham sedang libur, maka event date
pada penelitian ini menggunakan hari perdagangan aktif terdekat, yakni pada hari Senin
tanggal 24 Juni 2013.
Periode Waktu Penelitian
Gambar 3.1 Periode Waktu Penelitian (Estimation and Event Periods)
A D C B
EstimationPeriod EventPeriod
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
169
Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu
periode estimasi (estimation period) dan periode kejadian (event period). Periode
estimasi (estimation period) yang digunakan adalah selama 100 hari, yakni dari t-110
hingga -t-11 sebelum event day (tanggal 14 Januari 2013 - 7 Juni 2013). 10 hari event
period sebelum event date (10 Juni 2013 - 21 Juni 2013), 1 hari event date (24 Juni
2013), dan 10 hari event period setelah event date (25 Juni 2013 - 8 Juli 2013). Gambar
3.1. menunjukkan pembagian time horizon penelitian.
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitianini adalah seluruh emiten yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Menurut laporan IDX Fact Book 2013, jumlah keseluruhan emiten yang
terdaftar di pasar modal Indonesia adalah sebanyak 472 perusahaan. Dari keseluruhan
populasi tersebut kemudian diambil beberapa emiten untuk dijadikan sampel. Sampel
dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan yang masuk dalam daftar Indeks LQ-45
pada periode Februari-Juli 2013, saham sektor manufaktur, dan saham sektor
pertambangan. Pemilihansampeldilakukandenganmetodepurposivesampling, dengan
kriteria sebagai berikut:
1) Perusahaan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode
penelitian.
2) Perusahaan memiliki informasi harga penutupan harian (closing price) dan aktif
diperdagangkan selama periode penelitian
3) Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi (corporate action) selama periode
penelitian, seperti: stock split, right issue,merger, dan akuisisi. Hal ini untuk
menghindari bias hasil penelitian, karena aksi korporasi juga akan menimbulkan
reaksi investor.
Metode Pengumpulan dan Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersumber dari Bursa Efek Indonesia, Indonesian Capital Market Directory (ICMD),
BNI Sekuritas FEB UGM, dan Yahoo Finance. Data sekunder yang digunakan adalah
harga saham penutupan. Data mengenai aksi perusahaan (corporate action) diperoleh
dari Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
170
Penelitian ini menggunakan pengumuman-pengumuman resmi dari pemerintah
untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Selain itu,
Penelitian ini juga menggunakan berita-berita dari berbagai media massa nasional untuk
mendapatkan informasi terkait kenaikan harga BBM.
Pengujian Hipotesis I
a) Menghitung return realisasian (actual return) harian saham sampel penelitian:
, , 1
,
, 1
i t i t
i t
i t
P PR
P
b) Menghitung return pasar (market return)
Dalam penelitian ini, untuk menghitung return market saham sektor
manufaktur dan pertambangan digunakan harga penutupan IHSG. Sedangkan untuk
menghitung return market saham Indeks LQ-45 menggunakan Indeks LQ-45.
1
1
IHSG IHSGR
IHSG
t tMt
t
dan
1
1
Indeks LQ45 Indek LQ45R
Indek LQ45
t tMt
t
c) Menghitung return ekspektasian (expected return).
Dalam penelitian ini, expected return dihitung dengan menggunakan Single
Index Market Model, sebagai berikut:
i i Mt( ) .E(R )itE R
Koefisien α dan β diperoleh dari perhitungan persamaan regresi runtut waktu
antara return saham ( itR ) dengan return pasar ( MtR ). Dari koefisien α dan β tersebut
dapat dihitung expected return tiap-tiap saham ( )itE R.
d) Menghitung return taknormal (Abnormal Return)
, ,i t i t itRTN R E R
e) Menghitung Akumulasi Return Taknormal (Cumulative Abnormal Return)
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
171
10
, ,
10
ARTN RTNt
i t i t
t
f) Menghitung Rata-rata return taknormal (Average Abnormal Return) saham pada
hari ke t.
,a1 RTN
RRTN
k
iit
n
g) Menghitung akumulasi rata-rata return taknormal portofolio (ARRTN) atau
Cumulative Average Abnormal Return (CAAR).
10
,
10
ARRTN RRTN t
t i t
t
h) Menghitung signifikansi Abnormal Return dan Cumulative Abnormal Return.
,t
,
i,t
RTN RTNS
KSE
i
i t
KSE adalah kesalahan standard estimasi (standard error of the estimate)
untuk saham i selama periode T yang dihitung dengan menggunakan formula:
22
, ,
1
( ( ))
1 2
t
i j i t
j t
i
R E R
KSET
i) Menghitung Standardized Cumulative Abnormal Return (SCAR):
10
1 n
Nn
t
SCAR SARk
k = n- (-10) +1
Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa abnormal return tersebut secara
statistik signifikan tidak sama dengan nol (yaitu bernilai positif untuk kabar baik dan
bernilai negatif untuk kabar buruk). Uji t-statistic akan menunjukkan hasil bahwa
abnormal return bersifat signifikan bila t-hitung > t-tabel.
Pengujian Hipotesis II
Langkah-langkah untuk menghitung hipotesis kedua adalah:
a) Menghitung Average Abnormal Return:
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
172
1
,
10
t
before t
tbefore
AR
ARn
dan
10
,
1
t
after t
tafter
A
n
R
AR
b) Menghitung deviasi standar rata-rata return sebelum dan sesudah peristiwa:
12
10
(AR AR )
1
t
beforebefore
t
beforen
dan
102
1
(AR AR )
1
t
afterafter
t
aftern
c) Menghitung Uji statistik t (pada tingkat signifikansi α = 5 %)
2 2
AR ARafter before
after before
t
n n
d) Menentukan kriteria pengujian hipotesis
H0 ditolak jika
thitung> ttabel
H0 diterima jika
thitung< ttabel
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Sampel Penelitian
Dari 45 saham Indeks-LQ-45, sebanyak 8 perusahaan dikeluarkan dari sampel
penelitian karena tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel. Jumlah perusahaan sektor
manufaktur adalah sebanyak 137 perusahaan. Dari total sebanyak 137 perusahaan
tersebut, sebanyak 39 saham dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria. Jumlah
perusahaan sektor sektor pertambangan adalah sebanyak 36 perusahaan. Dari total
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
173
sebanyak 36 perusahaan tersebut, sebanyak 6 perusahaan dikeluarkan dari sampel
karena tidak memenuhi kriteria penentuan sampel. Ringkasan penyeleksian sampel
dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Seleksi Sampel Penelitian
Kriteria LQ-45 Sektor Pertambangan Sektor Manufaktur
Emiten terdaftar di BEI 45 36 137
Emiten Yang melakukan
Corporate Action 8 4 27
Emiten tidak aktif
diperdagangkan 0 2 10
Emiten Delisting/Belum Listing
2
Emiten yang dijadikan sampel
Penelitian 37 30 98
HASIL PENGUJIAN
Hasil Pengujian Hipotesis I
Saham Indeks LQ 45
Gambar 4.1. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return Taknormal
Saham Indeks LQ-45
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
174
Dari gambar 4.1. dapat dilihat bahwa rata-rata abnormal return mengalami
pergerakan positif dan negatif. Akumulasi rata-rata return taknormal (cumulative
Average Abnormal Return) mengalami pergerakan fluktuatif, tetapi pergerakan tersebut
selalu berada di angka negatif. Akumulasi rata-rata return taknormal negatif pada
periode kejadian ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap peristiwa
kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013. Informasi kenaikan harga BBM tahun 2013
dapat dikategorikan sebagai bad news bagi investor.
Tabel 4.3. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return
Taknormal Saham Indeks LQ-45
Keterangan: * signifikan pada α = 5% (t>1.688 untuk pengujian dua sisi dengan k
besar)
Tabel 4.3. menunjukkan nilai rata-rata return tak normal untuk saham Indeks
LQ-45 dan pengujian signifikansi di hari-hari periode peristiwa. Dari pengamatan
terhadap abnormal return saham Indeks LQ-45 didapatkan hasil bahwa terdapat
sembilan hari bursa yang menghasilkan abnormal return signifikan bagi pemegang
saham. Pada 10 hari sebelum peristiwa, abnormal return yang signifikan terjadi pada t-
Hari ke TglRRTN
(Average AR)
RTNS
(SAR)
ARRTN
(CAAR)SCAR
-10 10-Jun-13 -0.007347293 -1.741784485 * -0.007347293 -0.251404935
-9 11-Jun-13 -0.010758883 -3.082301607 * -0.018106175 -0.696296851
-8 12-Jun-13 -0.009239102 -2.440071768 * -0.027345277 -1.048490874
-7 13-Jun-13 -0.00922992 -2.332460834 * -0.036575198 -1.385152596
-6 14-Jun-13 0.006304793 1.690137274 * -0.030270405 -1.141202294
-5 17-Jun-13 0.003818749 0.920793805 -0.026451656 -1.008297156
-4 18-Jun-13 0.005817439 1.297206289 -0.020634216 -0.821061556
-3 19-Jun-13 -0.00305385 -0.52407343 -0.023688067 -0.89670504
-2 20-Jun-13 -0.002196728 -0.612485409 -0.025884795 -0.985109694
-1 21-Jun-13 -0.007911119 -2.858492447 * -0.033795914 -1.39769754
0 24-Jun-13 -0.006146279 -1.520175072 -0.039942193 -1.617115912
1 25-Jun-13 0.00990492 2.779627655 * -0.030037273 -1.215911218
2 26-Jun-13 -0.001335442 -0.375832036 -0.031372715 -1.2701579
3 27-Jun-13 -0.003076597 -1.039356501 -0.034449312 -1.420176089
4 28-Jun-13 -0.00566756 -1.056956309 -0.040116872 -1.572734591
5 1-Jul-13 0.005677433 1.685197613 -0.034439439 -1.329497267
6 2-Jul-13 -0.002399123 -0.644688416 -0.036838563 -1.422550025
7 3-Jul-13 -0.007484396 -2.264523085 * -0.044322959 -1.749405778 *
8 4-Jul-13 -0.002920561 -0.765560043 -0.04724352 -1.859904852 *
9 5-Jul-13 -0.003517267 -0.789196143 -0.050760788 -1.973815504 *
10 8-Jul-13 -0.006811972 -2.207237605 * -0.057572759 -2.29240281 *
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
175
10,t-9, t-8, t-7, t-1 (negatif) dan t-6 (positif). Pada 10 hari setelah peristiwa, abnormal
return yang signifikan terjadi pada t+7, t+10 (negatif), dan t+1 (positif).
Tanda abnormal return yang tidak konsisten sebelum peristiwa menunjukkan
bahwa pasar modal Indonesia mengalami kondisi ketidakpastian. Hal ini dikarenakan
kepastian pemerintah untuk memberlakukan harga BBM yang baru belum diketahui.
Nilai abnormal return positif signifikan sehari setelah peristiwa (t+1) menunjukkan
bahwa investor merespon positif kejelasan kebijakan pemerintah dalam menaikkan
harga BBM ini. Namun respon positif tersebut tidak bertahan lama, abnormal return
yang signifikan kembali negatif pada t+7 dan t+10. Sebagian besar abnormal return
yang signifikan pada periode peristiwa adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
peristiwa kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 dianggap oleh pasar secara
keseluruhan sebagai bad news dan investor meresponnya secara negatif.
Saham Sektor Manufaktur
Gambar 4.2. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return Taknormal
Saham Sektor Manufaktur
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
176
Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa Rata-rata return abnormal return saham
sektor manufaktur mengalami pergerakan positif dan negatif. Akumulasi rata-rata return
taknormal (ARRTN) pada sepuluh hari sebelum peristiwa berfluktuasi, sedangkan pada
sepuluh hari setelah peristiwa cenderung mengalami penurunan. Tren akumulasi rata-
rata abnormal yang terus menurun dan bernilai negatif pada periode kejadian ini
menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap peristiwa kenaikan harga BBM
tahun 2013.
Tabel 4.4. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return
Taknormal Saham Sektor Manufaktur
Keterangan: * signifikan pada α=5% (t>1,66 untuk pengujian dua sisi dengan k besar)
Tabel 4.4 menunjukkan nilai abnormal saham sektor manufaktur dan
signifikansinya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebelum peristiwa kenaikan
BBM, terdapat 4 hari bursa yang menghasilkan abnormal return signifikan (negatif
pada t-9, t-3, dan positif pada t-4, t-2). Pada saat event date (t0) abnormal return negatif
signifikan. Setelah peristiwa kenaikan BBM, terdapat 4 hari bursa yang menghasilkan
abnormal return signifikan dan tandanya konsisten negatif (t+3, t+4, t+9 dan t+10).
Hari ke TglRRTN
(Average AR)
RTNS
(SAR)
ARRTN
(CAAR)SCAR
-10 10-Jun-13 -0.003996763 -0.916659598 -0.003996763 -0.087800066
-9 11-Jun-13 -0.022037903 -6.700668577 * -0.026034666 -0.729607715
-8 12-Jun-13 0.000577214 -0.81018435 -0.025457452 -0.807209302
-7 13-Jun-13 -0.003150574 -1.430412842 -0.028608026 -0.944218003
-6 14-Jun-13 0.002377422 0.944488273 -0.026230604 -0.853752434
-5 17-Jun-13 0.003476652 1.102451006 -0.022753952 -0.748156779
-4 18-Jun-13 0.005332507 2.040436707 * -0.017421445 -0.552718388
-3 19-Jun-13 -0.004717884 -1.918789569 * -0.022139329 -0.736505096
-2 20-Jun-13 0.00336326 2.806016556 * -0.018776069 -0.467737455
-1 21-Jun-13 -0.000717148 -0.67238792 -0.019493217 -0.532140537
0 24-Jun-13 -0.007157413 -1.765392258 * -0.02665063 -0.701234448
1 25-Jun-13 -0.001665548 -0.400817664 -0.028316178 -0.739625818
2 26-Jun-13 -0.000334409 0.473566754 -0.028650587 -0.694266349
3 27-Jun-13 -0.007345969 -2.327206265 * -0.035996556 -0.917172282
4 28-Jun-13 -0.006052952 -2.771220784 * -0.042049508 -1.182607093
5 1-Jul-13 0.002439828 0.576740715 -0.039609681 -1.127365351
6 2-Jul-13 0.000258458 0.369205729 -0.039351223 -1.092001856
7 3-Jul-13 -0.006482512 -1.441470252 -0.045833735 -1.230069666
8 4-Jul-13 -0.003458929 -0.914048319 -0.049292664 -1.317619616
9 5-Jul-13 -0.007195988 -2.917715274 * -0.056488651 -1.597086055
10 8-Jul-13 -0.005358154 -1.915131549 * -0.061846806 -1.780522388 *
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
177
Bahan bakar minyak memiliki peran penting pada perusahaan sektor
manufaktur, sehingga kenaikan harga BBM akan berdampak juga pada perusahaan
tersebut. Tanda abnormal return yang tidak konsisten sebelum peristiwa menunjukkan
bahwa saham sektor manufaktur mengalami kondisi ketidakpastian. Hal ini terjadi
karena belum ada kepastian mengenai kapan pemberlakuan kenaikan harga BBM,
sehingga membuat investor saham sektor manufaktur sulit mengategorikan peristiwa ini
(apakah peristiwa yang dapat diantisipasi atau tidak dapat diantisipasi). Pada saat event
date (t0) dan beberapa hari setelah event date, abnormal return yang signifikan
konsisten negatif. Hal ini berarti bahwa setelah adanya kejelasan kenaikan harga BBM,
investor saham sektor manufaktur meresponnya secara negatif karena menganggap
kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada saham sektor manufaktur.
Saham Sektor Pertambangan
Gambar 4.3. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return Taknormal
Saham Sektor Pertambangan
Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata return taknormal mengalami
fluktuasi naik dan turun. Secara umum trend akumulasi rata-rata return taknormal
mengalami fluktuasi naik dan turun. Meskipun akumulasi return taknormal
menunjukkan fluktuasi naik dan turun, tetapi nilainya masih berada pada wilayah
negatif (kecuali pada hari ke 10 sebelum peristiwa). Tren akumulasi rata-rata abnormal
bernilai negatif pada periode kejadian ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
178
terhadap peristiwa kenaikan harga BBM tahun 2013. Informasi kenaikan harga BBM
tahun 2013 dapat dikategorikan sebagai bad news bagi investor.
Tabel 4.5. Rata-rata Return Taknormal dan Akumulasi Rata-rata Return
Taknormal Saham Sektor Pertambangan
Keterangan: * signifikan pada α=5% (t>1.699 untuk pengujian dua sisi dengan k
besar)
Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hanya ada tiga hari bursa yang menghasilkan
abnormal return yang signifikan bagi para pemegang saham sektor pertambangan (t-9,
t-8 dan t+2). Abnormal return yang signifikan bagi para pemegang saham adalah
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni
2013 dianggap oleh pasar investor pemegang saham sektor pertambangan sebagai berita
buruk (bad news) dan investor meresponnya secara negatif.
Pengujian Hipotesis II
Hipotesis kedua dari penelitian ini menyangkut perbedaan rata-ratareturn
taknormal (abnormal return)sebelum dan setelah peristiwa.Untuk menguji hipotesis
Hari ke TglRRTN
(Average AR)
RTNS
(SAR)
ARRTN
(CAAR)SCAR
-10 10-Jun-13 0.002150303 0.833300223 0.002150303 0.130139631
-9 11-Jun-13 -0.007590335 -1.894510793 * -0.005440032 -0.165733247
-8 12-Jun-13 -0.015955571 -3.276445005 * -0.021395603 -0.677427989
-7 13-Jun-13 0.004563081 0.996195806 -0.016832521 -0.521848342
-6 14-Jun-13 -0.001743171 -0.775052123 -0.018575692 -0.642891148
-5 17-Jun-13 -0.001046965 0.012273625 -0.019622658 -0.64097433
-4 18-Jun-13 -0.005226829 -1.152772514 -0.024849487 -0.82100715
-3 19-Jun-13 0.001423968 0.084291769 -0.023425519 -0.807842988
-2 20-Jun-13 -0.002450495 -0.157815792 -0.025876014 -0.832489673
-1 21-Jun-13 0.000435993 -0.625468157 -0.025440021 -0.930171388
0 24-Jun-13 0.007015918 0.95803482 -0.018424103 -0.780551487
1 25-Jun-13 -1.27559E-06 0.602242346 -0.018425379 -0.686497034
2 26-Jun-13 -0.011808724 -2.010385649 * -0.030234103 -1.000466524
3 27-Jun-13 -0.002256336 -0.223504916 -0.032490438 -1.035372127
4 28-Jun-13 0.001122855 0.720610172 -0.031367583 -0.922831726
5 1-Jul-13 -0.002423064 -0.524594099 -0.033790648 -1.00475956
6 2-Jul-13 0.001362229 0.282877943 -0.032428418 -0.960581447
7 3-Jul-13 -0.001859785 -0.146010402 -0.034288203 -0.983384441
8 4-Jul-13 0.002961239 0.93817795 -0.031326963 -0.836865661
9 5-Jul-13 -0.000991494 0.582895249 -0.032318458 -0.745832717
10 8-Jul-13 -0.00207104 -0.773098771 -0.034389497 -0.86657046
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
179
kedua tersebut, dilakukan uji beda antara abnormal return sebelum dan setelah
peristiwa. Uji beda dilakukan dengan menggunakan metode paired sampel t-test.
Tabel 4.6. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Abnormal return Saham yang
masuk dalam Indeks LQ-45 Sebelum dan Setelah Peristiwa
Dari hasil uji beda abnormal return saham indeks LQ-45 sebelum peristiwa
dengan setelah peristiwa, didapatkan nilai t-hitung sebesar -0,611. Karena nilai t-hitung
(-0,611) lebih kecil dari nilai t-tabel (1,833), maka Ha ditolak. Nilai signifikansi (p-
value) adalah 0,556 lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak. Dari hasil uji beda tersebut
maka dapat simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal
return sebelum peristiwa dengan abnormal return setelah peristiwa.
Hari ke RRTN Hari ke RRTN
-10 -0,007347293 1 0,00990492
-9 -0,010758883 2 -0,001335442
-8 -0,009239102 3 -0,003076597
-7 -0,00922992 4 -0,00566756
-6 0,006304793 5 0,005677433
-5 0,003818749 6 -0,002399123
-4 0,005817439 7 -0,007484396
-3 -0,00305385 8 -0,002920561
-2 -0,002196728 9 -0,003517267
-1 -0,007911119 10 -0,006811972
Rata-rata -0,0034 Rata-rata -0,0018
Std. Dev 0,00659 Std. Dev 0,00549
Beda rata-rata
t-hitung
Signifikansi
Sebelum Setelah
-0,00162
-0,611
0,556
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
180
Tabel 4.7. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Abnormal return Saham
Sektor Manufaktur Sebelum dan Setelah Peristiwa
Dari hasil uji beda abnormal return saham sektor manufaktur sebelum
peristiwa dengan setelah peristiwa, didapatkan nilai t-hitung sebesar 0,524. Karena
nilai t-hitung (0,524) lebih kecil dari nilai t-tabel (2,62), maka hipotesis penelitian (Ha)
ditolak. Nilai p-value (0,613) > lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak. Dari hasil uji
beda rata-rata abnormal return saham sektor manufaktur, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum peristiwa
dengan return setelah peristiwa.
Hari ke RRTN Hari ke RRTN
-10 -0,003996763 1 -0,001665548
-9 -0,022037903 2 -0,000334409
-8 0,000577214 3 -0,007345969
-7 -0,003150574 4 -0,006052952
-6 0,002377422 5 0,002439828
-5 0,003476652 6 0,000258458
-4 0,005332507 7 -0,006482512
-3 -0,004717884 8 -0,003458929
-2 0,00336326 9 -0,007195988
-1 -0,000717148 10 -0,005358154
Rata-rata -0,0019 Rata-rata -0,0035
Std. Dev 0,00785 Std. Dev 0,00350
Beda rata-rata
t-hitung
Signifikansi
Sebelum Setelah
0,00157
0,524
0,613
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
181
Tabel 4.8. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Abnormal return Saham Sektor
Pertambangan Sebelum dan Setelah Peristiwa
Dari hasil uji beda abnormal return saham sektor manufaktur sebelum
peristiwa dengan setelah peristiwa, didapatkan nilai t-hitung -0,579 (lebih kecil dari t-
tabel).Nilai p-value (0,577) > 0,05, maka Ho diterima. Dari hasil beda tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa rata-rata abnormal return saham sebelum peristiwa secara
signifikan tidak berbeda dengan rata-rata abnormal return saham setelah peristiwa.
KESIMPULAN
Dari hasil tersebut diatas, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
peristiwa kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 mengakibatkan timbulnya
abnormal return bagi para pemegang saham di Bursa Efek Indonesia secara
keseluruhan (yang dilihat dari sampel saham Indeks LQ-45). Peristiwa kenaikan harga
BBM tanggal 22 Juni 2013 juga mengakibatkan timbulnya abnormal return bagi para
dan pemegang saham sektor manufaktur dan sektor pertambangan. Hasil analisis uji
beda dua rata-rata menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan
signifikan antara variabel harga saham sebelum dan setelah peristiwa, baik untuk saham
Indeks LQ-45, saham sektor manufaktur dan saham sektor pertambangan. Hal ini
menunjukkan bahwa harga saham (yang dicerminkan oleh rata-rata return yang diterima
Hari ke RRTN Hari ke RRTN
-10 0,002150303 1 -1,275593255
-9 -0,007590335 2 -0,011808724
-8 -0,015955571 3 -0,002256336
-7 0,004563081 4 0,001122855
-6 -0,001743171 5 -0,002423064
-5 -0,001046965 6 0,001362229
-4 -0,005226829 7 -0,001859785
-3 0,001423968 8 0,002961239
-2 -0,002450495 9 -0,000991494
-1 0,000435993 10 -0,00207104
Rata-rata -0,0025 Rata-rata -0,0016
Std. Dev 0,00589 Std. Dev 0,00402
Beda rata-rata
t-hitung
Signifikansi
Sebelum Setelah
-0,00095
-0,579
0,577
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
182
investor) secara cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return sebelum dan setelah peristiwa.
DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Untung dan Siddharta Utama. (1998). Uji Efisiensi Bentuk Setengah Kuat pada
Bursa Efek Jakarta. Usahawan, No.03 (Maret), hal. 42-47.
Asri, Marwan. (1996). U.S. Multinational's Stock Price Reaction to Host Country's
Govermental Change: The Case of Prime Minister Takeshita's Resignation.
Kelola, Vol. 5, No. 11.
Bursa Efek Indonesia. (2010). Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek
Indonesia: Indonesia Stock Exchange.
Bursa Efek Indonesia. (2013). IDX Fact Book 2013: Indonesia Stock Exchange.
Cong, Rong-Gang., Yi-Ming Wei., Jian-Lin Jiao., Ying Fan. (2008). Relationships
Between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis From
China. Energy Policy 36, 3544– 3553.
Faff, R.W., Brailsford, T.J. (1999). Oil Price Risk and The Australian Stock Market.
Journal of Energy and Finance Development, 69–87.
Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical
Work. Journal of Finance 25.
Hall, S G. dan Kenjegaliev A. (2009). Effect of Oil Price Changes on The Price of
Russian and Chinese Oil Shares. https://lra.le.ac.uk/handle/2381/7605
Harto, Prayogo P. (2000). Reaksi Harga Saham Dalam Peristiwa Politik Indonesia
(Studi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000). Jurnal Bisnis Strategi, Vol.5,
hal.84-94.
Hartono, Jogiyanto. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi 7 ed.).
Yogyakarta: BPFE.
Husnan, Suad., Mamduh M. Hanafi., dan Amin Wibowo. (1996). Dampak
Pengumuman Laporan Keuangan Terhadap Kegiatan Perdagangan Saham dan
Variabilitas Tingkat Keuntungan. Kelola, Vol.5 No.11 hal.110-125.
Jogiyanto, HM. (2010). Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu
Peristiwa. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
183
Jones, C.M., Gautam, K. (1996). Oil and the Stock Markets. Journal of Finance, Vol. 51
No.2, 463-491.
Kalra, Rajiv., Glenn V. Henderson Jr., dan Gary A. Raines (1993). Effect of The
Chernobyl Nuclear Accident on Utility Share Prices. Quarterly Journal of
Business and Economics, Spring Vol.32 No.2 hal.52-77.
Kompas. (2013, Juni 17). Inilah Hasil “Voting” Rapat Paripurna BBM, Kompas Online.
http://nasional.kompas.com/read/2013/06/17/22152226/Inilah.Hasil.Voting.Pari
purna.BBM. Diakses tanggal 3 Juli 2013.
Kritzman, Mark P. (1994). What Practitioners Need To Know About Event Studies.
Financial Analyst Journal, November-December, hal.17-20.
MacKinley, A. Craig. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of
Economic Literature, Vol. XXXV (March 1997) hal.13-39.
Mansur, Iqbal., Stephen J. Cochran., dan Gregory L. Froiro. (1989). The Relationship
between the Equity Return Levels of Airline Companies and Unanticipated
Events: The Case of the 1979 DC-10 Grounding. Logistics and Transportation
Review, December, hal.355-365.
Oberndorfer, U dan Ziegler, A. (2006). Environmentally Oriented Energy Policy and
Stock Returns: An Empirical Analysis. Center Of European Economic
Research. http://ideas.repec.org/p/zbw/zewdip/5472.html. Diakses tanggal 23
Agustus 2013.
Park, J., Ratti, R.A. (2008). Oil price shocks and stock markets in the US and 13
European countries. Energy Economics 30.
Republik Indonesia, DPR. (2012). RUU RI No.19 Tahun 2012 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
Republik Indonesia, Kementrian ESDM. (2013a). Peraturan Menteri ESDM Nomor 1
Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Jakarta.
Republik Indonesia, Kementrian ESDM. (2013b). Peraturan Menteri ESDM Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Untuk Konsumen Pengguna Tertentu. Jakarta.
Republik Indonesia, Presiden. (2013a). Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5
Tahun 2013 Tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan bakar
Minyak. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
Jurnal Cendekia Vol. 1, Desember 2013. ISSN: 2354-6778
184
Republik Indonesia, Presiden. (2013b). Undang-Undang Republik Indonesia No.15
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 2012
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
Republik Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden. (2013). Buku Pegangan Sosialisasi
dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian
Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013 Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan
Bakar Minyak.
Robert, Ang. (1997). Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Mediasoft
Sadorsky, P. (2001). Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies.
Energy Economics 23, 17–28.
Suryawijaya, Marwan Asri., dan Faizal Arief Setiawan (1998). Reaksi Pasar Modal
Indonesia Terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa
27 Juli 1996). Kelola, Vol.VII No.18, hal.137-153.
Susiyanto, Muhammad Fendi. (1999). The Impact of Bank Restructuring
Announcement on The Banking Stock Prices: The Cases of Indonesia‟s Banking
Reforms on March 13 1999 and The Issuance of Government Bonds on May 28
1999. Gadjah Mada International Journal of Business, Vol.1 No.2, hal.37-61.