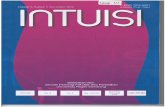HelmutWeber** - Jurnal UGM
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of HelmutWeber** - Jurnal UGM
POPULASI, 2(2), 1991
PENINGKATANPENDIDIKAN MASYARAKAT MINAHASADANDAMPAKNYA: TINJAUAN EKONOMI DAN SOSIAL*
Helmut Weber**
Abstract
Accordingto statisticaldata, theparticipationof the Indonesianpopulationintheformaleducationalsector is increasingrapidly. Onthe onehand, interms of quantity,this increase reflects a significant success of the Indonesiandevelopment polity. Butontheotherhand,themoreorlessuncontrolledgrowingnumberofhighlyeducated(which does not directly means highly skilled) people also contains a multitude ofproblematical impacts ondaily life,which are rarelydiscussed up to now.
Based on a more quantitatively oriented case study, which has been carried out
in the district Minahasa, North Sulawesi, we will discuss some aspects ofsocial-economic change onthevillage level,mainlycausedbythe development of theeducationalsector.Among others, the following aspectswillbe scrutinized indetail:the aspiration of the village people, monopolized by,formal education, education asan influential a) on monetarization of the household economy, b) onland-distribution, c) on employment problems and the composition of the locallabour force, d) onspatial mobility, and e) on investment bdhavior on the housholdlevel. Beside these more economic items, some significant social impactswill alsobediscussed, such as the relationbetween education and individualization, the spatialdistributionofthe family membersand its implications interms ofsocial; security, thedifferentiation of 'life-styles' and finally the alienation process between differentgenerations.
Pengantar
Studi kasus ini dipusatkan padaistilah 'aspirasi'. Dalam kontekspenelitian ini aspirasi berarti keinginanmasyarakat desa akan masa depandirinya dan generasi berikutnya, atau
harapan mereka terhadap tujuankehidupan. Peranan aspirasi dalamkehidupan sehari-hari bukan bersifatabstrak melainkan kongkret, sebabaspirasi mempengaruhi prosespengambilan keputusan rumah tanggadan cara pelaksanaan keputusan dalam
menyusun kegiatan-kegiatan sosial/ekonomis.
Penerapan aspirasi sebagai kategorianalis memberikan manfaat rangkap. Disatu pihak, aspirasi itu mencerminkanpersepsi/penyesuaian masyarakatterhadap perubahan sosial yang telahterjadi, di pihak lain penafsiranpelaksanaan aspirasi oleh si penelitiakan menggarisbawahi peranan aktifpara masyarakat sendiri dalam prosestransformasi sosial, sebab dalam
* Datayangdibahasdalammakalahinimerupakansebagianhasilpenelitiandari sebuahproyek kerja sama antara Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Manado dan FakultasSosiologi (JurusanSosiologiPerkembangan), UniversitasBielefeld,Jerman. Studikasusinidilaksanakan di Desa Kanonang, KecamatanKawangkoan, Minahasa.
*ÿ HelmutWeber, PhDadalahstafpeneliti Pusat PenelitianUGM.
45
POPULASI, 2(2), 1991
percobaan merealisasikan keinginanakan masa depan, masyarakat sendirimempengaruhi perubahannya, jadi dirimereka sendiri menjadi aktor sosial.
Secara umum, dalam kontekspenelitian ini, titik berat istilah aspirasimenyangkut bahasan tiga subtopik:1. PoiaAspirasi danAwal-Mulanya.
Pada awalnya didiskripsikan polaaspirasi yang paling menonjol ditempat penelitian, termasukawal-mulanya. Pertanyaan utama
yang perlu dijawab menyangkutinteraksi antara perubahanstruktural dan persepsi/penyesuaian masyarakat.
2. Dampak Strategi Pelaksanaandari Segi Ekonomi.Dibahas pengaruh pelaksanaanstrategi pendidikan terhadapperubahan ekonomi, baik di tingkatrumah tangga, desa, dan ekonomidaerah.
3- Dampak Strategi Pelaksanaandari Segi Perubahan Sosial.Ditanyakan sejauh mana aspirasi ituakan mengakibatkan perubahansosial, misalnya mobilitas, baikvertikal maupun horizontal,hubungan antara generasi, kontrolsosial, individualisasi, dansebagainya? Apakah pelaksanaantersebut menciptakan persoalan-persoalan sosial (socialproblems).
I. Daerah Penelitian: Pola AspirasiPenduduknya, Struktur NilaiSosial dan Ciri-Ciri EkonomiDesa
1.Aspek kuantitatif
Hasil penelitian tentang arah dantujuan aspirasi di desa penelitianmenunjukkan bahwa harapanmasyarakat desa terhadap masa depansangat didominasikan oleh keinginanmengikuti jalan pendidikanformalyang
sekaligus merupakan jalan vertikal didalam sistem stratifikasi sosial.Meskipun dari segi persentase tingkatpartisipasi dalam pendidikankelihatannya lebih kuat dibandingkandengan daerah-daerah lain, bagimasyarakat Minahasa aspirasi tersebutsebagai kecenderungan yang begitueksklusif. Keinginan meninggalkansektor primer (pertanian)yangdianggapterlalukasaruntukmenjadiwhite-collarworker, terutama di bidangpemerintahan, telah mempengaruhiproses pengambilan keputusan dalamrumah tangga-rumah tangga, juga disektor-sektor lain di Indonesia(bandingkan Effendi et.al 1990: 31,Notodihardjo 1990: 68; dan Murgianto1991. 66).
Ditanyakan pada masyarakat DesaKanonang tentang pekerjaan yangdiinginkan, baik kepada orang tua
maupun kepada para pemuda sendiri;sekitar 43 persen menyebutkanbertujuan mencapai sarjana untukmenjadipegawainegerigolongan tinggi,kurang lebih 20 persen memfavoritkanABRI, dan persentase hampir samamenginginkan sebagai pegawai swasta.Kurang lebih 9 persen mengutamakansebagai pendeta. Anehnya sama sekalitidak ada yang menyebutkan inginmenjadi petani, tukang, atau buruhindustri. Sebagian kecilsaja (dibawah 5persen) cenderung menjadi pedagangprofesional.
Pola aspirasi yang diarahkan padapeningkatan pendidikan formalmencerminkan kontradiksi antarakeinginan akan masa depan dan statusquo ekonomi desa. Nyata bahwapembagian tenaga kerja antarbidangmasih sangat rendah. Ekonomi desamasih tetap didominasi oleh sektorprimer; sekitar 86 persen dari seluruhrumah tangga berpendapatan dari
46
v
POFULASI, 2(2), 1991
sumber pertanian, baik sebagai petaniyang mempunyai tanah sendiri maupunsebagai buruh tani. Bidang pekerjaanlain, misalnya pertukangan ataupedagang profesional (berjual-beli)pada umumnya hanya sebagaipenghasilan sampingan.
TABEL 1.
PROF1LPEKERJAAN UTAMA
Pekerjaan Persentase
Petani 80,2BuruhTani 6,2Pertukangan 0,5Pegawai (negeri dan swasta) 7,0Pedagang 2,3Pengangkutan 0,5Penganggur/Pencari Kerja 2,1dan lain-lain 1,2
Pada Tabel 1. dimasukkan datasemua penduduk Kanonang yang tetaptinggal didesa.Jikaditambahkan dengansemua anak di atas usia 20 tahun yanglahir di desa, tingkat persentase pekerjasebagai pegawai naik lebih dari 100persen dan menjadi 15,6 persen. Darijumlah 15,6 persen tersebut, 45 persenhidup tetap di desa, 40 persen di ibukota Propinsi Manado, 11,6 persen ditempat lain diMinahasa, dan 3,4 persendiluar KabupatanMinahasa, terutamadiJawa.
Kecenderungan rakyat desa untukkeluar dari sektor pertanian dapatdicerminkan melalui perbandinganantara tingkat pendidikan masyarakatdesa keseluruhannya denganpersentase partisipasi pada sektorpendidikan menurut kelompok umur.
Jika dibandingkan tingkatpendidikan formal keseluruhanpenduduk Desa Kanonang pada Grafik1. dengan persentase murid/mahasiswa
sesuai denganusiadalamGrafik 2.,makaterlihat bahwa perkembangandibidangpendidikan nyata cukup signifikan. Halitu dikelompokkan menurut angkatanusia, partisipasi di bidang pendidikantingkat SMP naik dari 16,6 persenmenjadi 69 persen, tingkat SMA 23,3persen menjadi 62,5 persen, danperguruantinggidari7,8persenmenjadi14 persen.
2. Aspek Kualitatif: Faktor-FaktorPenyebab dan Prinsip 'JagaNama'
Ditanyakan tentang kemungkinan-kemungkinan aspirasi, bahwamasyarakat desa sendiri tidakmeragukan strategi pendidikan bagianak-anak. Seperti telah dijelaskanbahwa dalam wawancara mengenaimasadepanyangdiharapkanoleh orangtua terhadap anak-anak, hampir semuamenyebutkan pegawai (negeri) sebagaitujuan pertama. Selanjutnya, dalamklasifikasi white collar, jabatan sebagaidosen di Universitas Sam Ratulangisering diutamakan.
"Ya, memang kami ingin sekalimenyekolahkan anak-anak kami.Mungkin mereka berhasil danbisa menjadi pegawai negeri.Kami bekerja saja sebagai petani.Kami adalah orang sederhana,tetapi kami mencobamemperbaiki nasib bagi anakkami...""Bekerja sebagai dosen diUNSRATadalah sesuatuyang luarbiasa. Sampai sekarang kami didesa mempunyai beberapa anakyang bekerja di sana, dansungguh-sungguh kami banggasekali..." (Petani)Rasionalitas masyarakat desa
menghasilkan peningkatan pendidikandan mendorongperubahanyangsangat
47
A00 3
GRAFIK L
PERSENTASE TINGKAT PENDIDIKANMENURUT KEL0MP0K UMUR
GRAFIK 2.
PERSENTASE KESELURUHANNYA PENDUDUK YANG
TELAH MENGUNJUNGI LEMBAGA PENDIDIKAN
K)
$
5°
80
70
60
50
40
30
SMP SMA PT
(termasuk lulusan dan dropout) (termasuk lulusan dan dropout)
POPULASI, 2(2), 1991
pesat dari rumah tangga petani ke arahrumah tangga pegawai. Banyak penelitimengutamakanpertimbanganekonomissebagai faktor pendorong (misalnyaClauss/Hartmann 1981: 21, Karcher1985: 64, Benda-Beckmann F. dan K.1989:8,danBuchholt 1988:253)- Dalamstudi-studi tersebut, terutama gaji yangtetap, hak terhadap pensiun, bantuandalam keadaan darurat, dan 3-kemungkinan mendapat kredit lebihgampangdiperhitungkan sebagai aspek-aspek pertimbangan. Bagi masyarakatDesa Kanonang, jika ditanyakan lebihmendalam, mereka cukup sadarmengenai risiko dan bahaya ekonomisyang dikaitkan dengan strategipendidikan. Perhitungan berikutmenyimpulkan pandangan responden-responden di desa.1. Pengeluaran: mengikuti jalur
pendidikan formal memerlukansejumlah modalyang tinggi. Khususuntuk studi di universitas, biayayang perlu dipenuhi kurang-lebihantara 3 dan 4 juta rupiah (tahun1988).
2. Tenaga kerja: membebaskan anak-anak untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan mengurangipotensi tenaga kerja di rumahtangga. Dalam tradisi di pedesaan,peranan anak-anak sebagai pencarinafkah cukup besar (bandingkanWhite 1976: 271). Ketidakhadiran 4.anak-anak sebagai tenaga kerjasering perlu dikompensasikan, baikmelalui peningkatan pekerjaanorang tua/anggota keluarga sendirimaupun, terutama pada saat
menaburkan benih dan panen,dengan cara menyewa tenaga kerja.Dengan demikian, beban yangdipikul oleh rumah tangga berlipatdua, yaitu 1) peningkatankebutuhan cash untuk biayasekolah, dan 2) kenaikanpengeluaran rumah tangga untukmengupah tenaga kerja.Kesulitan masuk perguruantinggi: kemungkinan bagi anakuntuk menjadi mahasiswa semakinkecil '. Ketidakseimbangan antara
penyediaan tempat studi danpermintaan meningkatkanpersaingan antara calon-calonmahasiswa,danpersaingantersebutmewakili persaingan antara rumahtangga. Masaiah itu juga membawakonotasi ekonomis yang cukupbesar. Sesuai denganperkembangan ketidak-seimbanganya, ongkos studi 'luarbiasa' semakin naik dengan pesat,terutama untuk 'uang pelicin'.Dengan memburuknya kemungkin¬an menjadi mahasiswamelaluijalanbiasa, kemampuanuntukmembayar'uang ekstra' maupun hubungandengan 'orang dalam' menjadiprasyarat yang penting. Sebab itu,banyak keluarga dengan kondisiekonomis yang terlalu lemahterpaksakalahdalampersainganitu.Pengangguran: kemungkinansarjana menjadi pegawai semakinmerosot. Gejalainijuga dialamiolehmasyarakat desa. Sebagian lulusanPT yang menjadi penganggur, yang'sedang mencari kerja', atau yang
* Misalnya pada tahun 1991 sebanyak 1,3 juta lulusan SMTA dari seluruh Indonesia
memperebutkanhampir 110ribukursimahasiswabaruperguruantinggi negeridalamujian masuk perguruan tinggi. Jadi, hanya 8,4 persen dari jumlah calon itu akan
mendapat tempat studi di PTN.
49
POPULASI, 2(2), 1991
menerima pekerjaan tidak sesuaidengan harapan semakin besar.
| Persaingan terhadap lowongankerja semakin ketat sebab
I pertumbuhan jumlah sarjana1 sekaligus diikuti oleh penurunan| kemampuan pemerintah/lembagaI swasta untuk menerima pegawaij baru. Jadi, banyak anak desa yangi pulang ke desa (remigrasi?) sebabI pengangguransemakinnaik.Sejalanj dengan ketidakseimbangan antaraj lowongan dan permintaan kerja,
gejala uang pelicin menjadi bebanbesar, terutama untuk keluargaberpendapatan rendah.
5. Masalah pendapatan pegawai. Padaumumnya, gaji pokokyang diterimasebagai pegawai negeri (terutamagolongan Idan II) sering tidakcukup untuk memenuhikebutuhansehari-hari. Selalu terjadi bahwapegawai terpaksa harus mencaripekerjaan sambilan, selain itumereka (terutama sebagian yanghidup di kota) masih sering dibiayaikeluarga di desa.
limamasalahpokok tadi diakui olehmasyarakat berdasarkan pengalaman-nya. Meskipun pertimbangan strategipendidikan dari segi ekonomi kurangmeyakinkan, namun sampai saat initujuan aspirasi itu hampir tidakdiragukan. Dengan kata lain, perasaanpesimis terhadap jaminan ekonomistidak begitumempengaruhi kelangsung-an tujuan aspirasi.
Bagaimana keanehannya dapatdijelaskan? Yang merupakan dasar polaaspirasi masyarakat Desa Kanonangadalah salah satu interaksi antara adat-istiadat sebagai faktor tradisionaldengan keinginan meningkatkan posisidalam kedudukan melalui pendidikansebagai elemen baru. Berbeda daripendekatan klasik dari James Scott
50
(1976), rasionalitas petani tidak begituterbatas pada safety-first prinsip untukmenjamin subsistence-floor saja, jadibersifat statis. Sebaliknya, dalam studikasus ini aspirasi masyarakat desabersifat dinamis, jadi terbuka untukperubahan, baik dari segi ekonomimaupun dari segi sosial. Selanjutnya,teori populer kedua, yaitu pendekatandari pandangan political economyseperti diwakili olehPopkin (1979) jugaterlalu lemah untuk mengucapkankenyataan rasionalitas tersebut. Scottmenilai kekuasaan struktur nilai sosialtradisional terlalu tinggi dan tidakmemperhatikan fleksibilitas dalamperubahan norma sosial, sedangkanPopkin menggarisbawahi rasionalitasmodern bagi petani tanpa betul-betulmemberikan perhatian pada kekuasaannorma sosial dan perasaan persatuandalam kehidupan sehari-hari di desa.
Elemen baru terpenting yang telahmasuk ke dalam struktur nilai sosial didesa adalah kewajiban bagi masyarakatuntuk sukses, untuk meningkatkan tarafhidup. Lain apabila dibandingkandengan masyarakat yang lebihtradisional (bentuk Scott), di manaprinsip ascription masih lebih kuatdalam penentuan posisi sosial, prinsipachievement bersifat lebih dominandalam masyarakat Minahasakontemporer. Akan tetapi, perananprinsip achievement modern tersebuttidak dapat dipahami tanpa dikaitkandengan sebuah norma tradisional, yaituprinsip 'jaga naraa',
Dalam struktur nilai sosialmasyarakat desa (terutamabagigenerasitua), nama (reputasi) yang baik masihtetap merupakan dasar jaminan sosialdansekaligus ekonomis. Seseorangyangbekerja dengan baik, yang memenuhikeinginanlingkungansosial, yanghidupsesuai dengan norma sosial akan
POPULASI, 2(2), 1991
diterima dan dinilai tinggi olehmasyarakat; selain posisi sosial itu,sebagai pembawa nama yang baiksekaligus mereka berhak mendapatbantuan ekonomis, terutama dalamkeadaandarurat.Jika ditafsirkan denganpendekatan Pierre Bourdieu (1983),seorang sosiolog dari Prancis, namayang baik juga bersifat sebagai kapital,tetapi tidak langsung dalam bentukekonomis melainkan sebagai kapitalsosial. Akhirnya, kapital sosial itu jugadapat dimonetarisasikan misalnyauntukmendapat bantuan ekonomis dalamkeadaan kritis atau keunggulan dalampersaingan dengan seorang/keluargayang memegang nama yang tidak begitubaik (misalnya persaingan dalampembelian tanah dan sebagainya).
Dalam konsep masyarakat desa yangdibahas dalam makalah ini, kewajibanuntuk sukses difokuskan padapendidikan sebagai alat utama dalammobilitas vertikal. Seperti dijelaskantadi, keinginan masyarakat desa untukmengikuti jalan pendidikan tidakmerupakan jalur rumah tangga masing-masing, melainkan sebagian daristruktur nilai sosial. "Pendidikan masukadat", yang selalu disebutkan olehpenduduk di tempat penelitian,menunjukkan pada keterkaitan antara
norma sosial dan proses pengambilankeputusan. Mau atau tidak, rumahtangga-rumah tanggayang inginditerimaoleh lingkungan sosial harus mencobameningkatkan pendidikan bagi anak-anak setinggi mungkin. Melaluipartisipasi dalam "lomba pendidikan",nama keluarga bisa dijaga atau
diperkuat."Kami tidak hidup sendiri, kamihidupditengah masyarakat. Kamitidak bebas. Kami ingin diterimaoleh tetangga, keluarga, danteman-teman di sini. Semua
pendudukdidesainiinginsuksesdemikemajuan dalam kehidupan.... Semua mencoba menjadisebagian yang baik darimasyarakat. Kami mempunyainama baik yang perlu dijaga. ...Baik artinya bahwa kami tidakmenunggu sampai kamimendapatsesuatudarioranglain.Lebih baik memberi daripadamengambil. Seorang yang baikbisa menyesuaikan diri dengansyarat-syarat baru, dia harusbersikap murah hati, jujur,ramah, dan rajin. Terutama diaharus berpikir tentang masadepan, harus bekerja rajin untukmenyekolahkan anak-anak"(Petani)Prinsip "jaga nama" itu dewasa ini
bersifat dinamis, dalam arti'ketidakmajuan' yaitu kemunduran,kepuasan sebuah rumah tangga dengantingkat perkembangannya yang telahdicapai jelas akan dinilai negatif olehmasyarakat. Hasilstrategipembangunanrumah tangga telah menjadi sebagiandari 'nama' keluargadannamaituselaluperlu dibuktikan dengan hasil baru.
"Kami harus sadar tentangtuntutan-tuntutan darilingkungan sosial kami. Tidakselalu gampang memenuhi yangterduga. Semakin banyak hasilperkembangan semakin banyakyang diduga oleh lingkungannya.Jika kami menyekolahkan anakpertamasampaiperguruantinggi,pasti kami harus mencoba yangsama untuk anak-anak berikut-nya. Sukses itu dapat dianggapsebagai kebiasaan. Misalnyapadarumah tangga pegawai, terpaksaorang tua harus mengurus terus
supaya anak-anak mencapaitingkat pendidikan sama. Tidak
51
POPULASI,2(2), 1991
boleh bahwa seorang pegawaibilang: "Tidakperluterlalu lamadi sekolab. SMP saja cukup,pokoknya tabu baca dan tulis.Saya senang dengan anak yangmenjadipetani". (Guru SD)
3- Akar-Akar Aspirasi: Catatantentang Aspek Sejarah
Bagaimana proses 'pcndidikanmasuk adat' dari segi transformasimasyarakat? Menurut hasil wawancarabiografis dengan orang-orang yang tua
di desa, aspirasi masyarakat desaterhadap pendidikan telah sangatmenonjolpadazaman Belanda.Anggotamasyarakat yang menjadi pegawai,misalnya sebagai guru atau bekerja dibidang administrasi, sejak lama dinilaitinggi oleh lingkungan sosial karenadianggap bahwa mereka lebih pinterdan berpengalaman dibandingkandengan masyarakat petani. Hubunganantara penduduk Minahasa danpenjajah Belanda sejak dulu bersifatsangat positif, sebab pendatang-pendatang diterima sebagai pembawaagama Kristen dan kebudayaan, anggotamasyarakat yang bekerja sama denganpemerintah penjajah pada umumnyajuga dinilai sebagai sesuatu yangistimewa, yang mencerminkanmodernitas. Selain itu, dalam awalproses diferensiasi sosial, terutama
anggota-anggota dari keluarga yangberstatus tinggi secara tradisional(hukum besar, kepala suku, dukun/walian/tounaas, dll.) diterima sebagaimurid/mahasiswa. Hal itu disebabkanoleh strategi penjajah yang lebih
; memperhatikan keuntungan bagikeluarga yang berkharisma. Denganmengikat hubungan yang baik dengankeluarga yang strategis, maka rakyatbiasa lebih gampang dapat
diintegrasikan demi kepentinganpenjajah.
"Sejak dulu, seorang pegawaimerupakan sesuatu yang luarbiasa, meskipun di lihat dari segigaji cuma sebagian kecil diantaranya menjadi kaya. Tetapiyangmenjadipegawaiharus lamabersekolah, harus studi. Jadi diamembuktikan bahwa dia tidakhanya mampu bekerja di kebun,melainkan juga diamenggarisbawahi kepandaiandan kerajinan. Diabelajar banyakdan tahu banyak tentang yangterjadi di dunia. Sebab itu,mereka sangat kami hormati.Kami bangga sekali jika seorangdari anggota keluarga kamimenjadi pegawai...""Dulu, pada zaman Belanda,memangtinggi sekali status sosialseorang pegawai. Mereka banyakberasal dari keluarga berkuasa.Kalaudia lewat jalan rayadi desa,semua anak lari karena malu dantakut bertemu dengan dia. Semuadi sini menghormati seorangpegawai, dan mereka sendirimemberikan banyak bantuanterhadap perkembangan desakita. Tetapi dari segi statusekonomi keadaan mereka tidakselalu baik. Terutama antara
zaman PERMESTA dan awalORDE BARU banyak pegawai disini berhenti kerja, karenapendapatan terlalu kurang. Gajiseringbaru cukup untuk beli tigaliter beras. Meskipun demikian,status merekaselalu tinggisampaisekarang sebab mereka telahmembuktikan kerajinan dankepandaiannya" (Petani).Meskipun aspirasi yang diarahkan
pada tujuan pendidikan telah sangat
52
POPULASI, 2(2), 1991
kuat pada zaman Belanda, ongkosnyawaktu itu terlalu mahal, terutartia untuksekolah Belanda dan sekolah lanjutan.Sebab itu, seleksi murid/mahasiswaketat sekali. Hanya sejumlah kecil darianak desa ada kemunginan dapat masuksekolah, dan beban bagi keluarganyawaktu itutelah cukup berat.
"Kakak saya pernah masuksekolah Belanda. Tetapi karenabiaya begitu tinggi, terpaksa kamimenjual banyak tanah dan semuaanggota keluarga harus kerjakeras hanya untuk biayanya.Jugaterjadi bahwa beberapa keluargamenjual semua tanah. Tetapijarang, karena pada umumnyakami terlalu miskin. Selainmasalah uang jumlah kursi disekolah terlalu kurang. Dalamsatu tahun sebanyak 400 orangmencalonkan tetapi hanya 7yangditerima....M(Ibu A./Petani/PedagangKecil).Meskipun demikian, pendidikan
dasar (dalam arti bebas buta baca danbuta tulis) pada tahun 1930 jauh lebihberkembang di Minahasa daripada didaerah-daerah. lain di Indonesia.Misalnya persentase untuk Jawa danKalimantan pada tahun itu baru sekitar5 persen, di Sumatera 10 persen, diSulawesi Utara keseluruhannya kuranglebih 30 persen, dan Minahasasedikit dibawah 40 persen (bandingkan Jones1977: 67). Sebagai kecenderungan, datatersebut menunjukkan bahwa sejarahpendidikan di Minahasa lebih panjangdibandingkan dengan daerah lain, danselanjutnya statistik itu menggaris-bawahi efisiensi dalam perkembanganbidang pendidikan, yang terutama
digunakan oleh penjajah Belandasebagai alat kristianisasi .
Seperti telah dijelaskan, meskipunkemajuan di bidang pendidikan dasarcukup pesat di Minahasa, pembagiankemungkinan memasuki sekolahlanjutan masih kurang merata, terbataspada keluarga berkuasa dan yangberstatus strategis. Akibatnya adalahterjadi ketidakseimbangan antara
aspirasi dan kemungkinan. Ketidak¬seimbangan tersebut semakinberkurang sesudah kemerdekaan,terutama sejak awal Orde Baru. Hal itudisebabkan oleh:( a) perluasan sektor pendidikanformal
yang berarti, yaitu rasio antara
jumlah penduduk dan penawarantempat pendidikan semakin baik(sekarang semakin merosot lagi).
b) dibandingkan dengan zamanBelanda ongkos untukmenyekolahkan anak lebih rendah,dan
c) peningkatan pendapatan rumahtangga melalui moneterisasi danjuga sebagaihasildarirevolusihijau.
II. Pelaksanaan Aspirasi danDampaknya dari Sudut Ekonomi
Keinginan menyekolahkan anaksebagai salah satu strategi epidemismempengaruhi struktur ekonomi segalatingkat, baik di tingkat ekonomi rumahtangga maupun ekonomi desa dandaerah.
Pengaruh tersebut paling tampakpada rumah tangga yang berhasilmenyekolahkan anak-anak keperguruan tinggi. Sampai tingkat SMA,ongkos yang dikaitkan denganpendidikan belum begitu signifikan,
* - Tentangperkembangan dandiferensiasisistempendidikanformalpadazaman Belanda
bandingkan Kroeskamp 1974 dan Buchholt 1990.
53
f POPULASI, 2(2), 1991I\ sebab jarak antara desa dan sekolah-
sekolah SMA (yang terletak di ibu kota; kecamatan) tidak terlalu jauh. Padaj sekolah-sekolah di bawah perguruanf tinggi, biaya pendidikan, transport,
asrama, makan, dan lain-lain belumterlalu mahal.
Dengan mem,asuki perguruan tinggi,maka ongkos rutin bagi seseorangbertambah pesat. Selain terjadi ketidak-seimbangan antara lowongan tempatstudi dan permintaannya, mahalnyastudi diperguruantinggimengakibatkanperbedaan antara persentase muridSMA menurut kelompok umur (62,5'persen) dan persentase mahasiswa (14persen) di Desa Kanonangmencolok.
1. Moneterisasi Ekonomi RumahTangga
Salah satu aspek ekonomis yangdiakibatkan oleh perkembanganpendidikan adalah pengembanganmoneterisasi ekonomi rumah tangga.Peningkatan kebutuhan pendapatanmoneter untuk memenuhi ongkospendidikan menjadi faktor pendorongterpenting terhadap transformasi dariekonomi rumah tangga dalam bentuksubsistensi dan moraleconomy ke arahekonomi pasar. Bagian produksi
j casb-crop penanaman tanah khusus1 untuk pemasaran, semakin besar, dan] sebaliknyaperananproduksisubsistensiJ terbatas pada percobaan mengurangij pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya| rasionalitas terhadap temak sapi danj babi (ataukuda)sebagaibentukjaminanS sosial/ekonomis tradisional sering
digantikandanmenjadiasuransi ongkospendidikan.
Menurut hasil penelitian kami(Weber dkk, 1989) sesuatu yang seringterjadi (selain peningkatan pemasaranhasil pertanian dan penjualan temak)adalahpenjualantanahuntukmendapatmodal. Dengan penjualan tersebut,makajaminan ekonomis dirumahtanggapertanian semakin merosot secaralangsung; Sebab luas pemilikan tanahpada umumnya agak sempit , sehinggapenjualan tanah membawa bahayacukup tinggi. Jika diperhatikan adakemungkinan dihadapi masalahpengangguran yang semakin besar bagilulusan perguruan tinggi, stabilitasekonomi rumah tangga semakin lemah.Kalau sebagian tanah telah dijual dananak sebagai penganggur, makakemampuan menjamin kelangsungankehidupan semakin merosot.
2. Mobilitas Kawasan
Selain moneterisasi ekonomipedesaan, pemilikan tanah, danpeningkatan ketergantungan ekonomirumah tangga di kota kepada bantuandari pedesaan, mobilitas kawasanmerupakan salah satu dampak lain lagiyang sangat menonjol.
Peningkatan tingkat pendidikanmendorong perpindahan pendudukdari pedesaan ke kota. Pergeseranpenduduk ditandai dengan pendudukmemasuki perguruan tinggi sebabsemua lembaga diletakkan di kota,terutama di Manado dan sebagian kecildi Tomohon. Komposisi arus pegeseranpenduduk itu tidak terbatas pada
1 * Menurut sensus kami, pembagian tanah per rumah tangga rata-rata 0.66 ha. ladangI (tanahkering).Darisemuarumahtanggadidesa 8,7persentermasukpetani tunawisma
j dan kurang-lebih 11persen memiliki lebih dari 2 ha. Sebagian besar (53,55 persen )
| mempunyai antara 0,3 dan 1ha.
54
POPULASI, 2(2), 1991
kelompok mahasiswa perguruan tinggidan lulusannya. Angkatan tenaga kerjayang berpendidikan SMP dan SMAmerupakan potensi bermigrasi yangcukup besar. Kerendahan tingkatdiferensiasi ekonomi desa antara petanidanpegawaimendorongsebagianbesardari kelompok pencari kerja luar sektorpertanian untuk meninggalkan desa.Selain itu, rumusan semakin tinggipendidikansemakinrendabkeinginanmengikuti pekerjaan yang dianggapkasar dapat dibuktikan dengan jelas.Menurut hasil penelitian ini, juga dalamkelompok lulusan SMP dan SMA yangtidak mampu melanjutkan pendidikan,hampir tidak ada yang ingin menjadipetani, buruh, atau tukang. Sebagianbesar mencari pekerjaan di bidangadministrasi, sebagian kecil di sektorlalu lintas dan jasa lain.
Gejala tersebut menciptakanmobilitas penduduk rangkap dua.Sebagian besar dari rakyat desaberpendidikan menengah dan tinggitelah atau akan pindah ke perkotaan.Eksodus angkatan tenaga kerja itumendorong arus migrasi kedua, yaitumobilitas kawasan antara desa yangbelumlamamulai.Arus migrasi tersebutdibagi dua, baik sebagai tenaga kerjamusiman maupun sebagai penggaraptanah secara tetap, berdasarkan atas
prinsip bagi hasil antara keluarga yangmemiliki tanah dan keluarga yangbekerja;biasanyasebagian darikeluargaluas akan dipanggil ke desa sebagaitenaga kerja tetap.
Komposisikelompokyangmengikutiperpindahan permanen lain dapatdibandingkan dengan komposisipekerjaan musiman. Kemerosotanpenyediaan tenaga kerja untukpekerjaan 'kasar' di KabupatehMinahasa sendiri menarik 'impor'tenaga kerja dari kabupaten-kabupaten
tetanggadengantingkat perkembangan/kemajuannya lebih rendah, terutama
dari Bolang-Mongondow danKepulauan Sangir-Talaud. Permintaantenaga kerja dari daerah-daerahtersebut juga didorong oleh perbedaanharga pekerjaanyang jauh lebih rendahbagi tenaga kerja luar Minahasadibandingkan dengan tenaga kerja dariMinahasa sendiri.
3. Keterkaitan antara EkonomiRumah Tangga Pedesaan danAnggota-Anggota Keluarga diKota
Salah satu aspek ekonomi lagiadalahketerkaitan ekonomis antara bagiankeluarga yang ditinggalkan di pedesaandan bagian lain yang bekerja di kota.Berdasarkanhasilpenelitian ini, terlihatketergantungan seseorangyang bekerjadi sektor formal dikotakepada bantuandari jaringan sosial. Dengan data daristudi kasus ini, maka hipotesis dapatdibuktikan, bahwa sektor formal (dalamkonteks terutama pada tingkat pegawai)sering didukung oleh ekonomipedesaan. Sebagian besar rumahtanggadari Desa Kanonang yang pindah keManado belum mampu hidup mandiri.Tingkat moneterisasi dalam rumahtangga di kota sangat tinggi sebabhampir semua kebutuhan harusdipenuhi dengan uang. Bahan makananserta bahan bakar perlu dibeli di pasardan rumah pada umumnya harusdisewa. Selain itu, transport, biayasekolah, kesehatan, dan kebutuhan lainmemerlukan biaya secara moneter.
Berdasarkan atas latar belakangtersebut, maka bantuan yang diberikandari bagian keluarga yang masih hidupdi desa sangat berperan terhadapkelangsungan hidup bagi rumah tanggapegawai, baik dalam bentuk bahan
55
POPULASI,2(2), 1991
(sayur, beras, daging, dll.) maupundalam bentuk uang.
"Anak perempuan kami mengajardi SMP di Manado, suami diapekerja di Pelabuhan Bitung.Dua-duanya adalah pegawainegeri. Karena itu merekamempunyai pendapatan rumahtangga sangat baik dibandingkandengan rumah-tangga rumah-tangga pegawai lain di Manado.Tetapi mahal kehidupan diManado. Semua perlu dibayar,untuk rumah dan makanan,untuk apa saja. Juga ongkostransport mereka ke sekolah atau
ke Pelabuhan Bitung sangattinggi. Pada umumnya merekamampu memenuhi ongkostersebut. Tetapi untuk biayapendidikan perguruan tinggikemampuan mereka sangatterbatas. Karena itu, keluargaanak kami selalu dapat bantuan,baik bahan-bahan maupun uang.Kami masih mampu sebabkebetulan kami mempunyai satu
anak saja. Tahun lalu kamimenjualsatukolamikan berhargahampir satu juta. Hanya untukbiaya perguruan tinggi bagi duacucu. Selalu demikian" (Petani).
4. Kesimpulan Sementara
Sebagai asumsi dari analisis dampakaspirasi pendidikan dari segi ekonomi,maka dapat dikatakan bahwa lebihdaripada memecahkan persoalanketenagakerjaan, peningkatan tingkatpendidikan menciptakan masalahekonomis. Sebuah perbandingan antarasektor-sektor ekonomi masing-masingmenggarisbawahi ketidakseimbangandalam pembangunan ekonomiMinahasa. Seperti di Indonesia secarakeseluruhannya, peranan sektor
pertanian semakin turun, sedangkankenaikan persentase tenaga kerja yangditerapkan oleh sektor jasa tumbuhdengan pesat, tetapi sektor industripengolahan hampir belumdikembangkan dalamprosespergeseranantarsektor.
Pergeserantersebut disebabkanolehdua faktor. Pertama, dari segi aspirasidan struktur nilai sosial, penilaianterhadap pekerjaan, baik di sektorpertanian maupun di sektor industri(terutama industri kecil, juga pekerjaankasar di industri sedang dan besar)sangat rendah. Selain itu,perkembangan pendidikan di daerahMinahasa tidak menyediakan tenagakerja yang cukup berani, kreatif, danfleksibel untuk berwiraswasta. Kedua,yang mempengaruhi stagnasiperkembangan sektor sekunder adalahmasalah dalam bentuk akumulasi danrasionalitas investasi modal.Kemampuan (atau keinginan) untukmengumpulkan dana di tingkat rumahtanggamerupakanprasyaratyang sangatpenting terhadap perkembangan sektorindustri, baik secara kualitatif maupunkuantitatif.
Kalau ditafsirkan masalah modalinvestasi di tingkat rumah tangga diMinahasa, maka terlihat pengeluaranrumah tangga didominasikan oleh biayasekolah/studi. Secara kasar harusdibedakan antara dua kelompok rumahtangga. Yang pertamamempunyai statusekonomi terlalu rendah, baik untukmenyekolahkan anak maupun untukmengumpulkan modal investasi, yangdapat ditanam untuk mengembangkansektor ekonomi. Kelompok keduaadalah rumah tangga yang selisih antara
pendapatan dan pengeluaran cukupbesar, dengan potensi pengumpulanmodal sangat tinggi. Untuk kelompoktersebut, data menunjukkan ada
56
POPULASI, 2(2), 1991
pengaruh negatif ongkos pendidikanterhadap potensi mengakumulasikanmodal. Tanpa kecuali, scmua rumahtangga kelompok kedua yang ditelitimempergunakan lebih dari 50 persenkeseluruh pengeluaran khusus untukbiaya sekolah, sebagian sampai 80persen. Dengan demikian, rata-rata
kelebihan pendapatan setelahkebutuhan pokok dipenuhi dihabiskanmelaluiinvestasipadastratapendidikan.
Sebagai asumsi sementara harusdikatakan bahwa dalam keadaantransformasi ekonomi di Minahasadewasa ini, perkembangan pendidikantidak mendorong kemajuan dalam artipeningkatan diversifikasi dandiferensiasi antara tiga sektor ekonomi(pertanian, industri, pengolahan, danjasa). Dampak utama dari strategipelaksanaan aspirasi adalah penciptaansebuah klasifikasi diferensiasi sosialyang membedakan antara pekerjaankasar (petani, buruh industri,pertukangan, dll.) dan pekerjaan halus(ivitbe collor job). Persiapan paralulusan lembaga-lembaga pendidikanterutama diarahkan kepada tujuanpegawai/karyawan tetapi bukan untukmenjadimajikansendiri. Sebab itu,kamibisa bertanya bersama-sama denganDore:
"Is it any wonder, then, that theproductsof this kindof schoolingare not,when cooled out of theirmodern sector hopes and settledback ontheir farms, notablymoreinnovativeandsuccessful farmersthan those who have not been to
school? Is it surprising that thefrustrations of unemployedschool leavers and universitygraduates have not proved to bethat fructifying kind of tensionthat breeds the succsessfulentrepreneurs? The whole of
their schooling has conditionedthem to become employees. Thewhole of the modern sector is anemployee sector; its employeeteacher, the representative of themodern sector in the village,demonstrates the employeemodel in himself. The would-beemployee has learned to takeorders,not initiatives (Dore 1976:11).
III. Pelaksanaan Aspirasi danDampaknya dari Segi IlmuSosial
PerkembanganbidangpendidikandiMinahasa membawa beraneka-ragamakibat terhadap kehidupan sosial dipedesaan. Antara lain, kecenderunganke arah perpisahan antara tempat lahirdan tempat pendidikan (dengan katalain antara sosialisasi primer dansekunder) mempengaruhi peranankehidupan desa bagi penduduknya.Pada umumnya untuk bagian generasitua, desa masih tetap merupakari fokuskehidupan, baik dari segiketergantungan ekonomi maupunorientasi sosial. Bagi angkatan mudakepentingan desa dalam kehidupannyasemaldn merosot, terutama bagi merekayang telah pindah ke perkotaan untukmengikuti fase sosialisasi kedua.
Berdasarkan atas hasil penelitiankami, fiingsionalitas pendidikan formalsebagai katalisator dalam prosestransformasi sosial membawa tigadimensi:1. Pendidikan mendorong segregasi
kawasan antara anggota keluarga2. Pendidikanmendorongdiferensiasi
cara kehidupan3- Pendidikan mendorong gejala
keterasingan (alienasi) antar-
generasi.
57
I| POPULASI, 2(2), 19911i 1. Perubahan Sosialisasi danI| KeterasinganAntargenerasi1
Dalam wawancara mendalam,dimensi kedua dan ketiga selaludisebutkan, terutama oleh pendudukusia tua yang sering menilai sikapanak-anak desa sebagai kenakalan(deviance). Bersama-sama denganMead (1978) kami diharuskanmenyimpulkan bahwa diferensiasidalam sistem pendidikan mengakibat-kan pemisahan antara generasi. Tingkatpendidikanpemudayang rata-rata lebihtinggi daripada generasi tua
menciptakan semacam perasaansuperioritas (keunggulan) bagiangkatanmuda.Tetapiyangmerasa superior tidakmau lagi mengikuti peraturankehidupan yang dilakukan oleh bagianmasyarakat yang dianggap lebih rendah.
1 "Sebab anak-anak dewasa kini
J ikut pendidikan lebih lama, jelasmereka tahu lebih banyakdaripada orang tua. Mereka tahubaca dan tulis, menghitung lebihbaik dan biasanya tahu bahasaIndonesia lebih baik dibanding-kan dengan orang tua, apalagibahasa asing. Karena itu, seringmereka merasa unggul(sombong), mereka tidak mampulagi merasa bawahan terhadap
j orang tua dan tokoh-tokohj masyarakat,merekabikinapasaja| yang mereka mau tanpa merasaj malu. Mereka tidak mampu| menilai yang dibuat oleh orang| tuanya bagi mereka" (Petani)
Dalam masyarakat desa yang lebihmaju cara penyampaian pengetahuandan pengalaman (sosialisasi) paragenerasi muda sangat berubahdibandingkan dengan yang dialami olehgenerasi-generasi tua. Sosialisasi secara'alam' di tengah sistem reproduksikeluarga dan masyarakat di sekitamya
telah digantikan dengan perencanaanmasa depan secara eksplisit. Anak-anakmendapat posisi eksklusif yang lebihbebasdari tugas sebagai pencarinafkah.Sebaliknyamerekaseringdidukungolehkeluarganya untuk melanjutkanpendidikan.
"In the course of this processsocialization has turned intoeducation. What hadonce beenarather accidental byproduct ofthe early and multifariousintegration of children into thedemotic process of productionhas turned into the parents'central task of their life. Thisprocess can be explained on theone hand by the differentiationand therefore the growingcomplexity ofsociety, and, ontheother hand, by the growingcapability of the parents to facethe task of eduction as aconsciousplanningofthe infant'sprocess of development"(Schumacher/Vollmer 1982:259).Keputusan orang tua untuk
mendorong karier akademis bagi anak-anak membawa beberapa implikasiterhadap perubahan sosialisasi.Keluarnya mereka dari keluarga telahdimulai pada umur enam tahun denganmemasukilembagapendidikanpertama,yaitu SD. Data tersebut merupakanlangkah pertama (kecuali TK) dalamperjalanan desintegrasi rumah tangga;selain itu juga langkah pertama dalampembagian kerja antara yang dilakukantangan dan yang dengan pikiran. Orangtuamemegangtanggungjawab terhadapkelangsungan pendidikan melaluipekerjaan kasar, dan sebaliknyakewajiban bagi anak-anak untuk ikutmencarinafkahsemakin merosot. Selainpengetahuan ilmiah melalui studi di
58
POPULASI, 2(2), 1991
perkotaan, mereka menempuh sebuahgaya hidup (ilife-style) baru yang padaumumnya sangat berbeda dari carahidupyangmengatur 'duniakehidupan'orangtua.
Dampak dari diferensiasi sosialisasiberlipat dua. Di sisi satu, latar belakanguntuk mengumpulkan pengalaman danpengetahuan antargenerasi sangatberbeda, sama dengan tuntutanlingkungan sosial terhadap perilaku.Contoh, meskipun semakin lemah,mapalus (gotong royong) sebagainorma sosial memaksakan masyarakatdesa ikut serta dalam prinsip perilakutimbal-balik (reciprocity). Dengandemikian, stabilitas. masyarakat desatradisional (yang masih sangat berartibagi generasi tua di desa penelitian)berdasarkan atas kerja sama, atas
orientasi kearah kelompok. Perilaku itusering tidak sesuai dengan peraturan dilembaga-lembaga pendidikan formal;bukankerjasama melainkan persainganmenyusun perilaku sosial menuntutprestasi individual yang bukan kolektif.Perilaku timbal-balik adalah sesuatuyang dilarang, baik secara eksplisit(misalnya dalam ujian, tes, dll) atau
secara implisit dalam persaingan antara
mahasiswa untuk mendapat indeksprestasi yang baik. Sebagai akibat daripercobaan mencapai salah satu posisisebaik mungkin untuk meningkatkankemungkinan mendapatkan pekerjaan,makaprinsip kerja sama menghilangkanmanfaat dan menjadi disfungsional.Diukur dari segi tuntutan pamongdesa,juga dari segala tingkat pemerintahanbagi masyarakat untuk melestarianperasaan sosial, maka lembaga-lembagapendidikan formal, terutama di tingkatperguruan tinggi merupakan:
"places ofwrong learning. (...) Inthe imported institutions ofeducation these traditions are
discriminated against. Theprinciple of mutual help andcollective decision (gotongroyong), for example,traditionally is of greatsignificance in the Javanesevillage. In contrast to this, at
school the principleof individualachievements under conditionsof competition is stressed ... Thedropping out of an extremelyhigh number of pupils andstudents signals ... the culturalbreak. In other words, thisstrongly indicates an alienationfrom basic elements ofone's owntradition, which isbrought aboutby the mechanisms of theseinstitutions" (Karcher 1985: 60).
2. Transformasi Aspirasi: DariGenerasi Pengorbanan keGenerasi Konsumsi
Sesuai denganperubahansosialisasi,pola aspirasi menurut generasi jugamengalami transformasi cukupsignifikan. Pada umumnya orang tua didesamemproyeksikanaspirasi,harapan,dankeinginanpadagenerasiberikutnya.Kemungkinan meningkatkan statussosial bagi anak (dan karena itu 'nama'keluarga keseluruhannya) semakinrealistis jika orang tua bersikap cukuprajin, rasional, dan matiraga. Jadi,semacam dialektik antara matiraga/kerendahanhati dan peningkatanstatussosial merupakan realitas bagi banyakkeluargayang sukses.
"Betul, di desa kamihampir tidakada keluarga yang tidak merasakeberatan dalam percobaanmenyekolahkan anak. Tidak adayang kaya, semua harus kerjakeras. Hampir semua rumahtangga mempunyai beberapaanak. Dulu kami belum tahu
59
/
POPULASI, 2(2), 1991
banyak tentang KB. Orang tua
yang menyukseskan pendidikananak-anak selalu mengurusongkosnya. Mereka selalu pusingdan bertanya pada diri-sendiridari mana kami mendapat uanguntuk masa depan?" (Petani/Pedagang Kecil)Hasil wawancara pada generasi tua
membuktikan asumsi bahwa pekerjaandan tanggung jawab terhadap anggotarumah tangga dan lingkungan sosialmerupakan dasar kehidupan mereka.Pengetahuan tentang keluargaberencanamasih kurang dikembangkandan jumlah anak antara lima dansepuluh masih dianggap normal.Melahirkan anak adalah sebagian alamdalam kehidupan sehari-hari danbiasanya jumlah anak tidak menjaditujuan perencanaan.
"Dulu kami tidak memikirkantentang anak-anak. Bukan kamiyangmemutuskan tentangjumlahanak melainkan Tuhan. Kamiselalu senang dan gembira jikatambah satu lagi, meskipun darisegi nafkah setiap anakmeningkatkanbebankami... Kamihidup untuk anak kami" (Ibu S.Guru)Orientasi generasi tua sangat
berbedadibandingkandengan angkatanmuda. Program KB yang dipromosikanoleh pemerintah Indonesia sangatsesuai dengan keinginan sebagian besargenerasi muda yang lebih cenderungmeningkatkan kebebasan dan tingkatkonsumsi.
"Jika kami menikah kami kurangbebas. Kami tidak bisa ke mana-mana dan membutuhkan uanglebih banyak dan cuma sebagiankecil dari yang diinginkan dapatdipenuhi. Kami harus berpikirtentangkami sendiri supaya kami
hidup sebaik mungkin. Kalau adaanak semua akan berubah secaratotal. Karena itu tidak usahmenikah cepat" (Mahasiswi).Sesuai dengan kesimpulan
pernyataan-pernyataan dari sebagianbesar mahasiswa asal Desa Kanonang,makadapatdikatakanbahwajalan hidupyang diikuti oleh orang tua di pedesaankurangmenarik bagi mereka. Pekerjaansebagai fokus kehidupan, kewajibanuntuk mengebawahkan pada strukturnilai sosial, menyerahkan keinginanmenikmati kehidupannya, danmemfokuskan keinginan diri sendiripada generasi berikut tidak merupakansalah satu alternatif dibandingkandengan cara hidup yang lebih otonom
dan bebas."Memangsusah kehidupan orangtuakami. Selalubekerjaterus dansering mereka tidak mempunyaicukup makanan. Kebutuhan bagianak-anak selalu diutamakan...Mereka hidup di dalam rumahkayu dengan atap dan jendelayangrusak. Rumahsendiri terlalukecil, tetapi mereka tidak punyauang untuk membangun yangbaru. Semua digunakan untuksaya dan enam kakak-adik. Kamitidak ingin hidup seperti orangtua" (N., Laki-Laki, Drop Out)
3- MasalahJaminan Sosial
Untuk menyimpulkan dampak sosialperkembangan pendidikan formalterhadap hubungan antara generasi,perlu digarisbawahi lagi tentangkompleksitas keterasingan yang telahdibahas. Jika diikuti situasi orang tua dipedesaan, dibedakan antara tiga bentuksegregasi.1. Segregasi kawasan. Sebagai akibat
dari mobilitas penduduk yangditingkatkanmelaluiperkembangan
60
POPULASI, 2(2), 1991
pendidikan (sebagai salah satu
faktor yang sangat berperan antara
faktor-faktor lain, misalnya mediamassa, perkembangan lalu-lintas,dll.) semakin besar orang tua
ditinggalkan di desa.2. Segregasikebudayaan. Dengan latar
belakang sosialisasi danpengalamanyang semakin berbeda,bagian penduduk angkatan mudamenciptakan aneka ragam aspekkebudayaan baru yang sering tidaksesuai dengan keinginan/kebutuhan bagian keluarga di desa.
3. Segregasi ekonomi. Bentuk rumahtangga tradisional sebagaipersatuan ekonomis dan sosial danunit reproduksi semakin merosot.
Ada kecenderungan ke arahkeluarga inti.
Penilaian generasi tua terhadapmasalah jaminan sosial mencerminkankekuatiran terhadap masa depan yangkurangjelas. Lain dibandingkan dengangenerasi-generasi sebelumnya, merekaharus menyesuaikan diri dengankeadaan baruyang belum dikenal. Baikbantuan anak-anak dalam keadaandarurat (misalnya penyakit) dandukungan untuk hari tua maupunpelestarianekonomipertanian tidak lagidijamin sebab kekurangan tenaga kerja.
"Kami tidak tahu bagaimanakehidupankaminanti. Kami tetapsehat dan bisabekerja, meskipuntidak sama dengan dulu. Tetapibagaimana sesudah beberapatahun? Susahsewa tenaga kerjadisini. Anak-anak kami inginmembantu tetapi mereka tinggaldi kota, jadi tidak bisa... Jarangmereka ke sini, biasanya Mingguatau hari raya. Sering kami harusmembayar untuk perjalananmereka ke sini. Susah memang.Yangmudaberangkat ke kotadan
yang tua tinggal sendirian di sini"(Petani)Masalah jaminan sosial tersebut
menciptakan satu gejala yang sangatmenarik. Jaminan yang secaratradisional diberikan melalui bantuanintergeneratif (antaragenerasi) semakindiubah ke arah bantuan intrageneratif,bantuan antara anggota generasi tua
untuk menjamin reproduksi. Tolong-menolongserta bentuk-bentuk bantuantradisional lain meningkatkankepentingannya dalam bagianmasyarakat desa usia tua, yang merasasebagai 'teman senasib', bukan hanyadari segi integrasi masyarakat,melainkan lebih berperan dari segikelangsungan hidup.
"Dewasainiorangyangtua hiduplebih sepi dibandingkan dengandulu. Orang muda tidak merasatertarik berkomunikasi dengankami. Dulu anak-anak harusmembantu orang tua, prasyaratkeselamatan itu tidak pernahdiragukan, apalagi dalamkeadaan darurat. Pada zaman inikami yang tua harus salingmembantu. Kami tetap ikuttolong-menolong dan mapalus,baik di kebun maupun di bidanglain.Jika misalnya istri saya jatuhsakit dan tidak bisa masak,biasanya perempuan tetanggayang juga tua akan membantu...Dewasa inikami lebih tergantungpada generasi kami daripadaanak-anak kami" (Petani).
IV. Kesimpulan
Hasil penelitian di daerah Minahasadapat disimpulkan bahwa strategimengikuti jalur pendidikan setinggimungkin mengakibatkan beberapagejala yang bersifat problematis;kecenderungan asumsi itu dapat
61
POPULASI, 2(2), 1991
diterapkanuntukmasalah-masalahyangberkaitkan dengan perkembanganpendidikan di Indonesia secarakeseluruhan. Akibat-akibat dari sudutekonomi dan ilmu sosial yang telahdibahas dalam makalah ini membawabahaya frustrasi, salah satu perasaankekecewaan muncul di tempatpenelitian. Dasar frustrasi itu merupa-kan ketidakseimbangan antara harapandankenyataan.Jika tujuan aspirasi tidakdapat dicapai, maka sering merekamerasa gagal, malu, dan kehilanganmuka (nama), apalagi dalam kontekssosial di desa terpencil yang tidakanonim melainkan disusunoleh kontrolsosialyang ketat.
Alasan-alasan yang menciptakanfrustrasi sangat berbeda. Bagi kaumberpendidikan tinggi atau menengah,pengangguran menjadi alasan utama.
Dengan menjadi penganggur, makatingkat pendidikan yang telah dicapaitidak memberi manfaat, baik dari segiekonomi maupun dari segi status sosial.Dalam kasus tersebut semua terlibatdengan kekecewaan, baik si pencarikerjamaupunkeluarganya.
Kerendahanpotensiekonomi dalamrumahtanggadidesayangtelahdibahassering dapat ditingkatkan denganmasalah reintegrasi anak penganggurpada masyarakat desa. Sering terjadibahwa anakyang pulangtidak inginlagimenjadi anggota masyarakat sepertidulu, yang selalu diwajibkan ikut serta
mapalus, tolong-menolong, kerja bakti,dan kegiatan-kegiatan ekonomis yangtidak diinginkan. Mereka menjadi kaumkampungan, menjadi sebagian darimasyarakatdesayanghamshidupdalamkeadaan bersifat tradisional, meskipunkeinginanmereka lebihdiarahkan padajalan kehidupan lebih modern, lebihurban. Dalam masyarakat desa, kaumkampungan dinilai sebagai sub-culture,
sebab merekamempunyai struktur nilaisosial, norma, dan sikap yang sangatberbeda dari masyarakat. Tetapi mauatau tidak, masalah ekonomi mewajib-kanparapenganggur kembalike rumahtangga orangtua meskipunjarak mentalantara mereka dan masyarakat terlalujauh.
Dari segi perubahan sosialperpisahan antargenerasi - dan dengandemikian perubahan fokus aspirasi -palingmenonjoldanpalingberatdirasa-kan oleh orang tua. Meskipungejala itudipengaruhi oleh beberapa faktor(media massa, mobilitas kawasan, dll.),pendidikan formal dalam bentuk yangdibahas dalam makalah ini berperansangat besar. Dengan demikian, bisadiajukan pertanyaan bersama-samadengan pengakuan seorang tua di DesaKanonang:
"Sekarang kami sangat bingung,sungguh-sungguh. Duaanakkamistudi sampai menjadi sarjana,tetapi kemudian mereka tidakmendapat pekerjaan. Yangpertama mencari sejak tiga tahunyang lalu tanpa hasil. Dia tinggaldi rumah, tidak mau ikut orangtua ke kebun, tidak mau mem-bantu .....Terlalu kasar katanya.Dia nongkrong saja, suka kewaning untuk bertemu denganteman. Suka main dan minum.Apa yang bisa kami perbuat?.Kami adalah petani saja, orangsederhana tanpa pendidikan.Kami harus bergaul denganmasyarakat desa. Tetangga-tetangga selalu bertanya tentanganak-anak. Apakah merekamembantu,apakahmerekamasihke gereja?. Sungguh kami malu.Dan berapa tahun kami bekerjaterus untuk biaya studi. Tetapitidak tahu ke mana.. ." (Petani)
62
POPULASI,2(2), 1991
DAFTAR PUSTAKA
Benda-Beckmann, F.v. and K.v. 1989."Where structures merge: state and'off-state' involvement in ruralsocial security on Ambon. Paperpresented at the EIDOS-Conference, Amsterdam, March1989.
Bourdieu, P. 1985- "OnomischesKapital,kulturelles Kapital, sozialesKapital, in Kreckel, R. (Hrsg.),Soziale Ungleichbeiten. SozialeWelt, Sonderband 2, S. 183-198.
Buchholt, H. 1990. Kirche, Kopra,Burokraten. GesellschaftlicheEntwicklung und strategischesHandeln in Nord Sulatvesi/Indonesien. Saarbrucken/FortLauderdale.
Clauss, W., Hartmann, J. 1981.Agrarentwicklung in Indonesien -zwei Beispiele aus Nord-SumatraundJava. Working Paper No. 7 desForschungsschwerpunktsEntwicklungssoziologie derUniversitat Bielefeld.
Dore, R. 1976. The Diploma disease.Education, qualification anddevelopment. London
Effendi, Sofian, et al. Studi implikasisosial: peledakanpenduduk usiamuda. Yogyakarta: KerjasamaKantor Menteri NegaraKependudukan dan LingkunganHidup dengan Pusat PenelitianKependudukan,UniversitasGadjahMada.
Jones, G. 1977. ThepopulationofNorthSulatvesi. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
Karcher, W. 1985. "ZwischenModemisierungund Entfremdung:Stand und Tendenzen derHochschulausbildung inIndonesien", InternationalesAsienforum, 16 (1/2): 59-81.
Kroeskamp, H. 1974. Earlyschoolmasters in a developingcountry: a history of experimentsin school education in 19thCentury Indonesia.Assem.
Mead, M. 1978. Culture andcommitment: the newrelationships between thegenerations inthe 1970s.
Murgianto. 1991. Faktor-faktor yangberpengarub terhadappemanfaatan tenaga kerja usiamuda: studi kasus diKecamatanMadiun, Kabupaten Madiun,Jawa Timur. Tesis dalam ProgramS2 Studi Kependudukan, Jurusanantar Bidang, Fakultas PascaSarjana, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta. (Belum diterbitkan).
Notodihardjo, H. 1990. Pendidikantinggi dan tenaga kerja tingkattinggi diIndonesia:studi tentangkaitan antara perguruan tinggidan industri di Jawa. Jakarta:Ul-Press.
Popkin,S.L. 1979.Therationalpeasant:the political economy of ruralsociety in Vietnam. Berkeley:University of California Press.
Scott,J. 1976.Themoraleconomy ofthepeasant:rebellionandsubsistenceinSoutheastAsia. NewHaven:YaleUniversity Press.
Weber, H. 1991. Internal or externalorientation: the importance ofvillages incontemporary Minahasa,in Mai, U.; Buchholt, H. eds.:Continuity, change andaspiration:socialandculturallifeinMinahasa. Singapore: Instituteof Southeast Asian Studies. (Akanterbit).
63
POPULASI, 2(2), 1991
—.1991. "Searching for security inachanging world: the Indonesianconcept of development and itsimpact on the process of socialtransformation, in Mai, U.;Buchholt, H. eds.: Continuity,changeandaspiration:socialandcultural life in Minabasa.Singapore: Institute of SoutheastAsian Studies. (Akan terbit).
White, B. 1976. Production andreproduction in a Javanesevillage. Bogor.
64