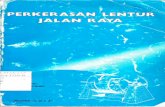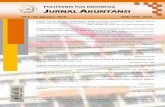Jalan Raya Pos: Daendelisme dalam Industrialisasi Jawa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Jalan Raya Pos: Daendelisme dalam Industrialisasi Jawa
Jalan Raya Pos: Daendelisme dalam Industrialisasi Jawa
Abstrak:Daendels dan para pewaris keyakinan visi industrialisasi menghasilkan
sederetan kolapsnya sistem sosial pada setiap rejim ekonomi
politiknya. Jalan Raya Pos Daendels mewarisi garis bantu
infrastruktur transportasi dan watak inheren proyek infrastruktur
raksasa. Pembangunan jalur transportasi sebagai alat atau syarat
pengembangan produksi selalu diikuti tindakantindakan kreatif
destruktif yang pelaku korbannya tetap rakyat.
Kata Kunci: Jalan Raya Pos, industrialisasi, Daendels, kolaps,
kreatifdestruktif
Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Daendels, atau Jalan Raya AnyerPanarukan hingga saat ini adalah salah satu poros utama transportasiPulau Jawa. Pada masanya jalan raya pos, memegang peranan pentingbagi perkembangan pulau jawa hingga hampir 2 abad. Meski perannyamulai tergantikan oleh ratusan kilometer jalan tol di beberapa ruasseperti MerakJakartaBogor, JakartaCikampekBandungCileunyi,Semarang, Gresik Surabaya, namun jalan raya pos adalah semacam garisbantu sketsa yang mendorong perkembangan seluruh cerita infrastrukturtransportasi P. Jawa dalam 4 dekade terakhir.
Yang unik dari cerita Jalan Raya Pos sang garis bantutransportasi Jawa adalah pujapuji dan hujatannya. Dalam banyakrujukan sejarah, Jalan Raya Pos yang dikembangkan oleh Daendels,selalu digambarkan sebagai kisah buruk bertinta darah. Pengorbanandua belas ribu kuli kerja paksa yang dikerahkan selalu digaris bawahidalam risalahrisalah tentang Daendels. Meski dihujat, para pengurusrepublik kepulauan ini bahkan warga negara kebanyakan pun merasa amatterbantu dan mengembangkan Jalan Raya Pos sebagai jalur utama P.Jawa. Bahkan proyek skala raksasa ini pun ditiru untuk mengembangkanruas jalan di bagian lain pulau yang dapat mempercepat perpindahanmanusia dan barang antar wilayah di pulau terpadat di dunia ini.
Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan tonggak penting dalamsejarah industrialisasi dan perdagangan Kepulauan Indonesia,khususnya Pulau Jawa. Ketika Jalan Raya Pos dibangun, bangsa Eropabersaing satu dengan lainnya untuk menguasai perdagangan dunia. Dalampersaingan dengan tujuan monopoli yang bahkan saling meniadakan satusama lain lewat peperangan, baik negara dan kongsi dagang,menggunakan segala kreatifitasnya demi memenangkan persaingan.
Demi memperoleh akumulasi keuntungan berkelanjutan, strategimempertahankan dan memperluas pasokan menjadi penting. Apa yangdilakukan Daendels dalam 3 tahun adalah tindakan sadar, sistematik,
bukan berupa respon survival seperti yang dialami VOC di abadabadsebelumnya.
Tindakan Daendels jauh lebih terencana dibandingkan niat dagangtradisionil ala VOC. Secara terencana, Daendels mengintegrasikankepentingankepentingan dagang dan industri, pertahanan, danadministrasi pemerintahan sekaligus. Dengan demikian dampak yangdihasilkan pun menjadi lebih luar biasa dibandingkan yang pernahdibuat oleh VOC dalam 200 tahun!
Konteks kontemporer yang memiliki ambisi serupa dengan Daendelsdan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda adalah pembangunan ruasjalan tol sepanjang 1000 km di awal administrasi Letjen (Purn)Soesilo Bambang Yudhoyono.
Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur (VOC) menaklukan danmenguasai sebagian P. Jawa sebagai respon atas gangguangangguanperdagangan oleh penguasa lokal. Keterlibatan VOC dalam percaturanpolitik P. Jawa, secara alamiah merupakan upaya bertahan dalammemenangkan monopoli perdagangan (Clive Day:1904). Jatuhnya wilayahPriangan, Pesisir Utara Jawa, dan Pesisir Timur Jawa merupakan satuproses transaksi politik elit lokal dan Belanda baik lewat diplomasi,intrik, maupun peperangan.
Tulisan ini, mencoba mengetengahkan perubahanperubahan yangdidorong oleh munculnya Jalan Raya Pos. Bagaimana jalan raya iniberperan dalam perubahanperubahan ekologis, sosial, politik demipertumbuhan ekonomi pada abad ke 19. Bagaimana ongkos sosial terciptadari perubahanperubahan tersebut di pelbagai bagian pulau Jawa. Danyang terpenting adalah bagaimana kesatuan wilayahwilayah berdaulatmencoba bertahan hidup dalam perubahanperubahan. Perkembangan lanjutdari berdirinya Jalan Raya Pos tak lebih dan tak bukan meneruskanambisi Daendels mengembangkan emporium bisnis atas ongkosongkos yangharus ditanggung rakyat. Di jaman Daendels dan para penerusnya,kapitalisme menemukan ruang ekspresi kreatifdestruktifnya.Perombakan sistem kehidupan besarbesaran, ditambah lagi perubahaninfrastruktur raksasa yang mendorong semakin cepatnya pengerukankekayaan tanah Jawa, dan perubahanperubahan berbiaya tinggi.
1. Letak Geografis Jalan Raya PosDalam bukunya, Jalan Raya Pos, Pramoedya menuturkan bahwa
Daendels sama sekali tidak membuat jalan baru dari Anyer kePanarukan. Daendels hanya memerintahkan melebarkan dan mengeraskanjalan hingga 7 meter. Sebagian besar jalan Anyer Panarukan telah adajauh sebelum Daendels tiba di P. Jawa 5 Januari 1808.
Tidak banyak catatan yang bisa ditemukan siapa yang membangunjalan penghubung pelabuhanpelabuhan di pantai utara Jawa. Meskipunjalur tersebut bukan jalur perdagangan maupun jalur militer utama,ekspedisi kerajaankerajaan di Jawa mulai dari jaman Majapahit hinggaVOC tiba menggunakan jalan tersebut untuk mengerahkan pasukan maupunberdagang (Raffles, 1811). Dalam beberapa catatan, jalur darat juga
merupakan sarana meraih akses kayu di hutanhutan demi pembangunankapalkapal, perumahan, dan pembukaan wilayah pesawahan padi(Peluso?).
Karena kondisi geografisnya yang landai, laut yang lebih tenang,Pantai Utara Jawa menjadi wilayah paling menjadi wilayah yang palingsibuk. Pelabuhanpelabuhan di Pantai Utara Jawa menjadi pintu gerbangarus keluar masuk Jawa dari dulu hingga saat ini. Sejarah mencatattumbuh dan tenggelamnya pelabuhanpelabuhan penting di Jawa sepertiBanten, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tegal, Semarang, Demak,Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya.
Jalan Raya Pos, atau jalan raya Daendels, atau Jalan AnyerPanarukan, berawal dari Anyer, pusat kesultanan Banten lama danberakhir di Panarukan, satu daerah di sebelah selatan Surabaya.Ketika Daendels membangun Jalan Raya Pos, rute utama justru tidakmengikuti garis pantai. Dari Batavia jalan raya pos berbelok ke arahselatan, ke arah Pasar Minggu menuju Bogor (Buitenzorg) terus ke arahCiawi, Puncak, Cianjur hingga ke Bandung.
Dari Bandung, Daendels memerintahkan Jalan Raya diteruskanmenembus pegunungan di daerah Sumedang hingga Cirebon. Mulai darisini, pembangunan Jalan Raya Pos konsisten mengikuti garis Pantai,menghubungkan pelabuhanpelabuhan di Pantai Utara Jawa.
Namun, sebagai infrastruktur utama Pulau Jawa, Daendels tidakhanya berpikir sebuah jalur di utara Pulau Jawa. Daendels jugaberpikir perlunya sarana jalan ke daerah pedalaman, ke pusatpusatkerajaan Mataram yang sama kaya dengan pantai utara. Menggantikanarah aliran barang yang dulunya menggunakan sungaisungai besarseperti Bengawan Solo, Brantas, Serang, Kalimas, dan Cimanuk yangdigunakan sebagai jalur keluar masuk barang dan manusia (Pratiwo:2002) (Raffles: 1818)
Jalur ke pedalaman sudah ada sejak lama, bahkan menjadi jalurutama kerajaankerajaan di Jawa yang umumnya berpusat di pedalaman.Salah satu jalan yang cukup terkenal adalah jalan raya Mataram. Jalanini menghubungkan pusat kerajaan Mataram ke Demak dan Jepara melaluiSalatiga (cek lagi).
2. Persaingan dagang hingga ke peperangan di JawaUntuk menghasilkan keuntungan berlimpah dari perdagangan dan
industri, ada sejumlah kata kunci yang tidak bisa dihilangkan;efisiensi dan ketersediaan pasokan bahan dan tenaga kerja, sertapasar. Sejarah menunjukkan seluruh revolusi perdagangan dan industriadalah upaya meningkatkan efisiensi, mempertahankan pasokan bahan dantenaga kerja di seluruh mata rantai industri, sambil terusmempertahankan dan memperluas pasar.
***Jawa adalah laboratorium raksasa emporium bisnis kerajaan
Belanda sekaligus pabrik komoditikomoditi dagang paling laris gula,kopi, teh, nila, dan tembakau di abad ke 19.
(tabel komoditi, stockdale, raffles, boomgard)
Peningkatan efisiensi, jaminan ketersediaan pasokan, danmenciptakan pasar membutuhkan dukungan pranata sosial. Emporiumbisnis manapun, amat memahami hal ini. Maka tak bisa dipungkiri,hingga saat ini, satu upaya dagang seringkali dilengkapi kekuatanpolitik dan militer. Tak heran, di akhir abad pertengahan, seluruharmada dagang Eropa diperlengkapi kekuatan militer.
Sejak jaman VOC (Verenidging OostIndische Compagnie), efisiensidan ketersediaan pasokan adalah problem utama yang harus diselesaikandemi memenangkan persaingan dagang diantara bangsabangsa Eropamaupun dengan kerajaankerajaan pribumi di kepulauan Nusantara.
Tetapi, Jawa begitu seksi. Letaknya yang strategis serta kondisikesuburan yang luar biasa membuat VOC bukan hanya membuka posperantara dan gudang di Pulau Jawa. VOC bahkan memindahkankonsentrasi upaya dagangnya dari Kepulauan Maluku ke Pulau Jawa.
Setelah mengobrakabrik Maluku dan sukses memonopoli perdagangandi belahan timur Nusantara, VOC mulai merambah Pulau Jawa. Kesuburandan hasil bumi rempahrempah Jawa jauh lebih produktif dibandingkankepulauan Maluku (stockdale, raffles).
Selain itu, kondisi politik pulau Jawa di abad ke XVII cukupmenguntungkan bagi pihak luar yang ingin menguasai perdagangan PulauJawa. Sengketa antar para raja mulai dari Banten hingga Blambanganmelawan Mataram tengah berlangsung. Peperangan terjadi di manamanaberebut pengaruh atas sisasisa kejayaan Majapahit.
Pada awalnya, VOC tidak memiliki kebijakan atau keinginan untukikut campur dalam sengketa elit kerajaankerajaan di Jawa. Tetapidemi mempertahankan suplai dan monopoli perdagangan, mau tidak mau,VOC menggunakan kekuatannya dan terlibat dalam gonjangganjingpolitik Jawa.
Sengketa berkepanjangan dan peperangan antar kerajaan di Jawadimanfaatkan VOC yang dengan mudah menaklukan Jaya Katra (atauJakatra) dari tangan Kesultanan Cirebon (tahun 1527). De Graafmencatat, sepanjang 2 abad kerajaankerajaan di Jawa sungguh diobokobok oleh kepentingan dagang Eropa sekaligus ambisi para elit kuasadi hampir seluruh bagian Jawa, bahkan hingga Madura dan Bali.
Sir Thomas Stamford Raffles mencatat dalam 2 abad bahkan hinggakedatangan kongsi dagang Eropa, Pulau Jawa diperintah oleh banyakkesultanan/kerajaan yang saling menyerang satu sama lain. KetikaPortugis tiba mengunjungi Pulau Jawa awal abad ke 16, KesultananDemak baru tumbuh dan sibuk melebarkan kuasanya ke Barat, Timur, danSelatan di pedalaman Pulau Jawa.
Ketika Belanda tiba di Sunda Kelapa, Kesultanan Mataram barumulai tumbuh dan berperang dengan kerajaankerajaan pesisir di Barathingga Timur. Tidak ada satu kesatuan yang kuat yang siap berhadapandengan arus balik (pramoedya: Arus Balik) ekspansi dari Barat. Pulau
Jawa terlalu sibuk menjadi panggung teater elitelit sisa kerajaanMajapahit.
(Tabel: Kronik Peperangan antar Elit di Jawa (Raffles) Gimonca)
Alhasil, sengketa antar kerajaan yang masih berkerabat inidimanfaatkan oleh VOC, British East India Company, dan Portugis.Kedatangan kongsi dagang eropa yang berniat memonopoli perdaganganrempahrempah dari Hindia Timur tidak menjadi picu bersatunyakesultanankesultanan yang ada di Jawa, bahkan di Nusantara.Persaingan antar kesultanan seringkali memanfaatkan kehadiran kongsidagang eropa ini untuk menghantam lawanlawannya, terutama sekali diabad 17 dan 18.
Sengketa yang seringkali berujung pada peperangan antar kerajaandan kesultanan tak lebih dan tak bukan adalah sengketa para elit.Dalam catatan sejarah masa lampau, pertarungan elit dicatat dengancukup detail oleh Raffles, yang kemudian dikoreksi oleh DeGraaf danPigeaud (1974).
3. Perombakan Kuasa di Jawa; pilihan atau paksaan? Melihat sejarah Jawa, pergantian dinastidinasti, bangkit dan
runtuhnya kerajaankerajan tak lain dan tak bukan adalah upayamerebut, mempertahankan, dan memperluas alir sumber daya, kekayaan,kejayaan, dan kesenangan. Pada beberapa peristiwa rajaraja Jawatampak antisipatif terhadap serangan pihak luar. Sayangnya tidaksetiap generasi mampu mempertahankan semangat dari pendahulunyabahkan emoh mengikuti. Bercokolnya VOC dan Hindia Belanda hingga 3abad, menjadi sebuah pilihan para elit yang bersengketa
****Setiap sengketa, konflik, hingga peperangan seringkali berujung
pada perubahan kuasa atas wilayah. Perombakan struktur kuasa,perubahan penguasaan atas warga dan tenaga kerja. Demikian juga yangterjadi di Jawa.
Sejak jaman dahulu peperangan menghasilkan dinastidinasti baru,pergeseran pengaruh wilayah, perubahan alir sumber daya danketersediaan tenaga kerja. Menguatnya kerajaankerajaan Islam dipesisir utara Jawa adalah contoh paling mengemuka. BerdirinyaKesultanan merubah lansekap kekuasaan kerajaankerajaan Hindu yangpada akhirnya runtuh lewat ekspansi persekutuan kerajaan Islampesisir ke seluruh penjuru Jawa.
Alir sumber daya yang dahulunya mengalir ke daerah pedalamanberhenti dan terakumulasi di wilayah pesisir. Pengislaman pendudukdilakukan secara masif sistematik, kadang dengan paksaan, dalamrangka pengalihan kesetiaan dari kerajaankerajaan lama; Majapahitdan Pajajaran. Semakin banyak penduduk Jawa yang diislamkan semakinbanyak pula yang beralih kesetiaannya pada wilayah pesisir. Selain
itu, peralihan kesetiaan ini tentunya merubah alir upeti danketersediaan tenaga kerja ke Demak.
(Tabel; peperangan dan perubahan penguasaan wilayah)Saling membantu dan saling menikam adalah sesuatu yang terus
terjadi sepanjang 2 abad di Jawa. Frederick dan Worden dalamIndonesia: A Country Study menulisnya sebagai perrenial instability,atau ketidakstabilan abadi. Sejak jatuhnya Majapahit hingga pecahnyaMataram, bisa dikatakan tidak pernah ada perdamaian antar elit diPulau Jawa.
Kebangkitan eropa di abad pertengahan dan upaya ekspansiperdagangan eropa ke Asia Tenggara, sempat dibaca oleh KesultananDemak yang baru bangkit. Upaya mencegah masuknya eropa yang akanmenyaingi perdagangan saudagarsaudagar islam di Nusantara dilakukanlewat penyerangan Pati Unus ke Malaka, 1511. Upaya ini gagal dan takpernah berlanjut.
Setelah kegagalan dan kematian Pati Unus, rajaraja islam Jawamemilih menyibukkan diri memperluas kekuasaan. Tak pelak lagipeperangan menyelimuti seluruh Jawa hingga berdirinya Mataram puluhantahun kemudian.
Ketika Mataram di Pedalaman mulai bangkit dan menolak membayarpajak ke Pajang di sebelah Timur Jawa dan mulai menyerang kerajaankerajaan pesisir, peralihanperalihan terus berlangsung. Peperanganmenyebar dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa, membentukkesetiaankesetiaan baru dan perubahan aliran sumber daya.
Mataram dibawah pimpinan Sultan Agung I sempat melakukanserangan besarbesaran ke Jakatra, Pos perdagangan VOC, dua kali ditahun 16281629. Serangan ini gagal, VOC tetap bertahan di Jakatrayang menunggu saatsaat penting menancapkan monopolinya di PulauJawa.
Sejak gagalnya serangan Sultan Agung ke Jakatra, Matarammemfokuskan dirinya ke arah timur menaklukkan kerajaankerajaan dipesisir seperti Gresik, Surabaya, Tuban, dan Jepara. Mataram bahkanmenutup seluruh pelabuhan di pesisir dari perdagangan.
Kampanye Mataram ke Timur bukan tanpa perlawanan. Peperanganberlangsung dari satu generasi ke generasi lain. Pada saatsaattertentu Mataram mencari bantuan pihak lain demi memadamkanpemberontakan. Dan bantuan itu datang dari VOC, yang pernah menjadimusuh Mataram di jaman Sultan Agung I.
Beberapa kali di abad ke 17 dan 18, Mataram meminta bantuan VOCmengatasi pemberontakan sisasisa kerajaan pesisir. Berkat bantuanVOC, Amangkurat I dari Mataram berhasil memadamkan pemberontakanTrunojoyo. Tetapi, tidak pernah ada bantuan gratis. Sebagai imbalanVOC mendapatkan hak monopoli atas gula, beras, dan opium sertawilayah nan subur di daerah Priangan.
Demikian pula yang terjadi di Kesultanan Banten. Sengketa elitkerajaan antara Putra Mahkota Banten Sultan Haji dengan Ayahandanya,
mengundang VOC terlibat. Hasilnya sudah dapat diduga, monopoliperdagangan dari Kesultanan Banten. Hingga akhir abad ke 18, Bantenbukan lagi pesaing VOC dalam perdagangan rempahrempah.
Sengketa antar kerajaan di Jawa berakhir di pertengahan abad 18dengan ditandatanganinya perjanjian Gianti (tahun 1755). Perjanjianini menegaskan kehadiran Kongsi Dagang Belanda secara mutlak bukansaja dalam rangka monopoli perdagangan tetapi juga perubahanperubahan tata kuasa wilayah secara dramatik. Setelah wilayahnyadiperkecil lewat penyerahan Priangan dan Pantai Utara, KerajaanMataram di bagi empat. Sementara itu Banten dan Cirebon berakhirsebagai wilayah boneka.
Kebebasan berdagang yang sempat dinikmati sebelum kongsi dagangeropa hadir, hilang. Para raja pun harus membagi keuntungannya kepadaVOC, meski tetap memiliki kuasa atas tenaga kerja. Tetapi hal initidak berlaku mutlak.
Banyak elitelit kuasa, seperti adipati dan bupati yang kecewabahkan disingkirkan saat kekuasaannya mengecil dan tidak memilikikebebasan berdagang. Namun tak sedikit pula yang justru menikmatihubungan dagang yang tidak seimbang ini. Harga beli yang rendahdibebankan kepada rakyat yang seringkali tidak menerima bayaran ataubekerja paksa menghasilkan panen tanaman komoditi kepada para bupati.
Walaupun kerajaankerajaan jatuh bangun, dan kesetiaankesetiaanpada ’yang dipertuan’ berubahubah, namun hubungan kuasa antara pararaja dan bangsawan tetap tidak berubah. Hingga akhir abad ke 19,Raffles mencatat langgengnya hubungan hamba dan tuan di kalanganmasyarakat Jawa. Pola relasi feodalistik desa dan pusatpusatkekuasaan, di mana desadesa memberikan upeti atau hasil panennyakepada raja tanpa diganti masih tetap berlangsung. Atas pemanfaatanrelasi feodalistik ini VOC mengeruk keuntungan yang besar dariperdagangan dengan para raja dan elit lokal.
Kongsi Dagang Belanda (VOC) pada dasarnya tidak memilikikebebasan menguasai tenaga kerja di seluruh Jawa. Pada beberapabagian wilayah seperti di daerah Priangan, VOC memberlakukanPrianganstelsel yang memaksa petani, lewat bupati dan adipati didaerah Priangan, menanam kopi di sebagian lahannya. Kopi ini kemudiandibeli oleh VOC dengan harga yang ditetapkan sepihak dan menjadisumber pemasukan penting bagi VOC. Di kemudian hari, GubernurJenderal mereplikasi Van den Bosch model Priangan Stelsel dalam tanampaksa (cultuur stelsel).
Di sebagian wilayah lain seperti di pesisir utara dan timur JawaVOC melakukan kesepakatankesepakatan dengan para raja tanpamenyentuh langsung urusan produksi di lapangan. Para raja atau bupatisetempatlah yang membangun mekanismemekanisme agar alir hasil bumi,dan rempahrempah tetap terjamin kepada VOC. Lewat struktur lokalyang feodalistik yang disokong oleh relasi tuan dan hamba, penguasapenguasa lokal mensuplai hasilhasil komoditi kepada VOC. Rakyat
dengan berbagai cara dipaksa menjadi penyuplai hasil bumi yangnantinya diserahkan kepada VOC.
Hingga abad ke 19, tidak tercatat munculnya perlawanan rakyatjelata kepada VOC ataupun kepada para raja. Rakyat tetap dalamkehidupan yang tak jauh berbeda dari jaman keemasan Majapahit, meskiarus sudah berubah, ke Jaman Neerlandica.
Runtuhnya Jawa adalah pilihan. Para elit politik Jawa begitusibuknya berperang dan bersaing hingga lupa adanya ancaman intervensidari luar. Elit Jawa memilih menikmati dan mempertahankan kesenangandan kekuasaanya sendiri dibanding melakukan kesepakatan dramatik demimempertahankan diri dari serangan luar. Posisi lainnya seperti ditulsoleh
4. Jalan Raya Pos, Fondasi integrasi industri JawaSebagai sebuah infrastruktur raksasa, Jalan Raya Pos adalah
manifestasi upaya integrasi kepentingankepentingan ekonomi, militer,dan pengurusan wilayah. Pembangunan Jalan Raya Pos bukan hanyapembangunan fisik, tetapi sebuah upaya sistematik perombakan ekologidan sistem politikekonomi Jawa menjadi lebih kapitalistik.Pengembangan infrastruktur pada era Daendels terjadi bukan hanya padasektor fisik, pekerjaan umum, pertanian, dan kehutanan, tetapi jugadi bidang hukum dan pemerintahan. Apa yang dibangun Daendels adalahsketsa awal pengembangan industrialisasi Jawa di masamasasesudahnya.
***Jalan Raya Pos dibangun pada saat persaingan dagang dan industri
eropa memuncak. Revolusi industri yang didorong oleh ditemukannyamesin uap dan moda perekonomian baru atas tenaga kerja bebas danpasar mendorong sejumlah revolusi di Eropa.
Di akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19, eropa sedang bergolak,Napoleon Bonaparte dari melakukan kampanye menaklukkan negaranegaratetangganya termasuk Belanda. Peperangan di Eropa terutama pertikaianantara Inggris dan Perancis menjalar hingga ke negerinegeri jajahantermasuk kepulauan Nusantara.
Kemajuan ekonomi Inggris dan kemampuannya menguasai jalurperdagangan laut di dunia mengharuskan Prancis mempertahankan seluruhwilayah yang mampu mendukung perekonomian perang. Kerajaan Belandayang saat itu berada dibawah penaklukan Perancis, kebagian tugasmempertahankan pusatpusat produksinya di seluruh dunia termasuk Jawadari serangan Inggris.
Inggris yang bercokol di Bengkulu (?) dan Malaka adalah ancamanbagi kelangsungan perdagangan Belanda di Nusantara. Kekalahan armadaPrancis di Teater Eropa menghasilkan siasat baru untuk mempertahankandaratan. Apalagi saat itu, Jawa adalah pulau terkaya di dunia yangmembuat VOC menjadi parastatal terkaya di dunia (sumber: tanyaArief).
Marschalk Herman William Daendels, seorang perwira Belanda yangbertugas pada angkatan perang Napoleon, ditugaskan oleh Raja Belandakala itu, Lodewijk Bonaparte, mempertahankan pulau Jawa dari seranganInggris.
Daendels hadir di Pulau Jawa berhadapan dengan kekacauanadministrasi dan kepemerintahan peninggalan VOC yang korup, merugi,dan dibubarkan 1799. Sistem administrasi VOC yang mengandalkanmonopoli perdagangan saja tanpa melakukan kendali langsung atasproduksi. VOC mengandalkan hubungan dan paksaan kepada pribumipenguasa wilayah yang menjual hasil bumi. Sementara itu, perkembangancorak produksi yang berkembang di Inggris dan negerinegerijajahannya mampu memberikan keuntungan. Sementara VOC mengalamikerugian menerus akibat korupsi pejabat VOC dengan elitelit Jawa.
Daendels dengan segala ambisi dan keteguhannya, mengukuhkankembali kekuatan politikekonomi BelandaPrancis di Pulau Jawa. Dalamsejarah kiprah Belanda di Hindia Timur, Daendels adalah GubernurJenderal resmi yang benarbenar mewakili Raja Belanda untukmenjalankan pemerintahan di Hindia Timur sebagai negeri 'jajahan'(Burger: 1962). Daendels secara sengaja dan sungguh,merestrukturisasi sistem politik warisan VOC. Struktur pemerintahanyang ada dan kekuasaan serta kewenangan yang masih dimiliki olehrajaraja dan adipatiadipati Jawa dapat menghambat misi BelandaPrancis membangun pertahanan pantai Pulau Jawa.
Dengan segera Daendels melibas hambatanhambatan akibat kolusipejabatpejabat VOC dan penguasa lokal. Sistem pemerintahan yangcenderung otonom di masa VOC diganti menjadi terpusat dengan modelpegawai negeri. Seluruh rajaraja maupun penguasa wilayah pribumitidak diperkenankan memungut sendiri hasil bumi dan membagi ataumenjual hasilnya kepada Belanda. Administrasi Belandalah yangmengelola pengambilan hasil bumi; gula, kopi, nila, dan lada termasukkayu jati. Rajaraja dan pribumi penguasa wilayah dijadikan pegawaiyang menerima gaji yang tunduk dan patuh pada majikannya. Lewatsistem ini pula, Daendels memerintahkan para raja dan bupati diseluruh Jawa mengerahkan rakyat untuk menjadi kuli kerja paksa danmemaksa rakyat menyerahkan hasil panen berasnya untuk memasok panganbagi para kuli dan mandormandor pembangunan jalan.
Hubungan Belanda dan penguasa pribumi tidak lagi berkaitandengan dagang, tetapi sudah menjadi tuan dan kaki tangannya. Dengandemikian, sebagai Gubenur Jenderal, Daendels berhak dan berwenangmemerintahkan para penguasa pribumi mengerahkan budak, dan berasuntuk membangun Jalan Raya Pos, atau De Grote Postweg, atau La GrandeRoute, dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km dan diselesaikandalam waktu 1 tahun!
Operasi perlucutan kekuasaan adalah agenda penting untukmemenuhi kebutuhan kulikuli pembangunan jalan dan penyediaan suplaimakanan. Tidak semua wilayah bersedia menyerahkan hakhak istimewasebagai rajaraja yang mendapat bagian dari perdagangan dengan VOC.
Penguasapenguasa pribumi menanggapi tindakan Daendels bermacammacam. Tercatat sejumlah wilayah melakukan perlawanan terbuka. Namunada pula yang pasrah dan bersedia dilucuti tanpa perlawanan, danpatuh mengerahkan rakyat membangun jalan raya pos sambil menikmatikucuran gulden gaji pegawai kerajaan Belanda.
Beberapa upaya perlawanan terhadap instruksi Daendels terjadi diBanten. Penolakan Kesultanan Banten untuk mengerahkan rakyat bagipengembangan jalan dari Anyer ke Batavia berakhir dengan takluknyaBanten.
Perlawanan sengit juga terjadi di sekitar Sumedang. PangeranKornel menolak dan berperang melawan Daendels yang memaksa dibukanyajalan di daerah cadas di dekat Sumedang. Perlawanan Pangeran Korneldipatahkan, dan ribuan rakyat dipaksa membuka salah satu ruastersulit sepanjang jalan raya pos.
Perlawanan frontal dari dua wilayah, Cirebon dan Banten berujungpada dihapuskannya kesultanan Banten dan Cirebon. Wilayah keduadiambil alih oleh administrasi Belanda.
Daendels memang hanya 3 tahun berkuasa, namun keberadaannyasungguh menghasilkan horor bagi penduduk yang dilalui Jalan Raya Pos.Sepanjang 3 tahun tersebut, setidaknya 12 ribu orang tewas kelaparan,kelelahan, akibat kerja paksa (rodi) melebarkan jalan raya. Angka iniadalah angka yang sempat dicatat oleh administrasi Inggris di jamanraffles. Tidak pernah ada angka pasti jumlah manusia yang tewas saatmembangun Jalan Raya Pos.
(tabel jumlah korban di beberapa wilayah, sumber buku Jalan Raya Pos,Toer)
Jalan Raya Pos bukan hanya menelan rakyat pribumi. Puluhanpejabat kulit putih turut menjadi korban akibat kelelahan danpenyakit malaria serta kolera. Batang, di Jawa Tengah sekarang,adalah salah satu wilayah yang paling banyak mengalami korban jiwa.Nama Batang sendiri berarti mayat, untuk mengenang neraka jalan rayapos.
Tetapi apakah karya Daendels hanya berhenti pada infrastrukturjalan raya saja?
Daendels tidak hanya bermimpi menjalankan tugas kemiliterannya.Secara resmi jabatannya adalah Gubernur Jendral yang wajib menguruskoloni agar bermanfaat bagi Kerajaan Belanda. Bawahan Daendels (CliveDay:1904) menulis bahwa Daendels memaksa penduduk asli dan para elitkuasa lokal mengerahkan tenaga kerjanya bukan hanya untuk perdagangantetapi juga pekerjaanpekerjaan umum seperti infrastruktur jalan,untuk pertahanan, biaya rutin para pejabat serta berdirinyadepartemendepartemen pemerintahan.
Selain membiayai persiapan perang, Daendels ditugaskanmenunjukkan kepiawaiannya menambah pundipundi kerajaan Belanda yangkala itu berada di bawah protektorat Prancis. Produksi tanamanperdagangan tetap menjadi pilihan Daendels.
Daendels paham surutnya pemasukan kas bagi kerajaan Belandasalah satunya disebabkan oleh korupsi dan pungli pegawaipegawai VOCdan para bupati. Daendels memutus pertalian yang rentan pungutan inilewat tindakantindakan perlucutan. Namun, Daendels tidak hanyamembersihkan dan merubah sistem pemerintahan dan perdagangan yangrentan pungutan menjadi lebih efisien. Lebih dari itu, Daendelsmemperluas wilayah produksi tanaman seperti kopi di sepanjang Pantaiutara Jawa.
Bahkan, demi menjamin keberlangsungan pasokan kayu, Daendelsdengan sengaja mencabut kewenangan Bupati Rembang dan Jepara atashutan jati di wilayah tersebut. Daendels membentuk semacam departemenkehutanan yang bertugas merawat dan memastikan pasokan kayu jati padakebutuhankebutuhan Belanda.
Di jaman inilah secara mutlak Belanda berkuasa pada sebagianbesar wilayah Jawa, kecuali sisasisa kerajaan Mataram yang masihmemiliki keistimewaan terbatas sebagai protektorat. Pada jaman iniDaendels melakukan klaim bahwa tanahtanah di luar tanahtanah privatdan kerajaan Mataram adalah milik kerajaan Belanda. Integrasikepentingan kapital dikerjakan secara sungguh dan memberikan fondasibagi perkembangan industrialisasi selanjutnya.
Peperangan dan persaingan yang semakin tajam antar kerajaankerajaan di Eropa disertai gagasangagasan modern atas akumulasikapital menyertai Daendels yang diharuskan mempertahankan Pulau Jawasambil terus mengakumulasi keuntungan. Daendels mengubah watakpemerintahan ala VOC menjadi pemerintahan yang tersentralisasi danmenciptakan landasan industrialisasi lewat pembangunan infrastrukturfisik, perluasan lahan produksi, modifikasi corak pengerahan tenagakerja, perubahanperubahan struktur politik, sistem peradilan, danpemberlakuan pajak. Waktu berkuasa yang singkat membuat Daendelstidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Sebagian hanya berupaprinsipprinsip yang kemudian dikembangkan, dimodifikasi olehgubernurgubernur jenderal Inggris dan Belanda selanjutnya, Raffles,Van der Cappelen dan Van den Bosch (Clive Day:1904) (van Zanden).
Tetapi apa yang dilandaskan oleh Daendels menjadi fondasiperubahanperubahan lebih lanjut di Pulau Jawa yang selalu memberikeuntungan berlipat ganda bagi perdagangan Kerajaan Belanda,dinikmati oleh elitelit lokal jawa, dan mengorbankan wargakebanyakan.
5.Jalan raya pos pada akhirnyaPaska pembangunan Jalan Raya Pos, Pemerintah Hindia Belanda
mendapat keuntungan mutlak dari infrastruktur maha besar pada jamanitu, Jalan Raya Pos. Di sepanjang Jalan Raya Pos bertumbuhlah kotakota yang menjadi pospos ekonomi industri perkebunan dan pabrikpabrik pengolahnya. Nas dan Pratiwo (2002) menulis bagaimana JalanRaya Pos ternyata mendorong terbentuknya Jawa sebagai kota terpanjangdi dunia. Jalan raya Pos merubah konfigurasi pemukiman ekonomi yang
dahulunya berbasis sungai ke basis jalan. Peran sungai sebagai saranamobilitas ditinggalkan dan menurun. Menurunnya peran sungai dalamkehidupan penduduk Jawa berdampak tidak terurusnya wilayah sungaihingga terjadi pendangkalan di sejumlah sungai penting di Jawa Baratdan Jawa Tengah. Sejumlah pelabuhan tradisionil di muara sungaiseperti Lasem ditinggalkan sejak jalan raya pos berdiri. Jalur lauttidak lagi menjadi jalur utama perdagangan. Semua beban akibatindustrialisasi jatuh ke darat.
Sayangnya tidak ada studi lanjut dampak tidak diperhatikannyasungaisungai sebagai sarana penting kegiatan manusia.
Perubahan besar yang juga terjadi adalah perluasan perkebunankopi, tebu, dan nila di wilayah di sekitar Jalan Raya Pos sertaseluruh industrialisasi yang menyokongnya. Jalan Raya Pos tidaksecara serta merta memberikan akibat langsung pada perubahanperubahan drastis ekologi, kehidupan sosialpolitik, dan ekonomiJawa. Tetapi hal yang patut diingat, Daendels menanamkan prinsipprinsip integrasi infrastruktur fisik, administrasi pertanahan,perindustrian, hukum, dan tata pengurusan wilayah dalam sekali pukul.
Para penerus Daendels, suka atau tidak suka, menggunakan danmemodifikasinya terus menerus hingga industrialisasi terus memberiuntung bagi Hindia Belanda dan sejumlah kecil elit di Pulau Jawa.Sementara itu ongkosongkos eksperimen industri terus menerusditanggung rakyat dari jaman ke jaman.
6. Ongkosongkos eksperimen industrialisasi
Paska Daendels, upayaupaya perluasan industri di bawahadministrasi Hindia Belanda dilakukan sistematik. Setelah Rafflesmeninggalkan Jawa, tahun 1819 hingga 1830 adalah uji cobaindustrialisasi, kepatuhan dan ketertiban ala penguasa baru, HindiaBelanda. Tahun 1830, dalam kondisi yang penuh utang dan pembelajaranatas penguasapenguasa terdahulu Gubernur Jenderal Van den Boschmenjalankan misi Hindia Belanda yang sesungguhnya, mengurus Jawasebagai alat produksi yang memberi keuntungan bagi Kerajaan Belandademi membayar utangutang terdahulu dan membangun kembali KerajaanBelanda yang porak poranda akibat perang Eropa.
Van den Bosch menerapkan sistem kultur (cultuur stelsel), ataudikenal sebagai tanam paksa, yang mewarisi nafas Daendels membangunindustrialisasi Jawa. Van den Bosch tinggal mengikuti apa yang telahditinggalkan Daendels, secara fisik maupun prinsipprinsippengembangan industrialisasi. Perluasan perkebunan lewat tanam paksa menemukan tanah subursetelah Daendels mengembangkan jalur transportasi baru, klaimsebagian besar tanah Jawa sebagai milik Raja Belanda, perlucutankuasakuasa lokal menjadi kaki tangan resmi Kerajaan Belanda, danpenerapan peradilan kontinental.
Bagian ini memamparkan sejumlah analisis faktual perubahanperubahan sosioekologik Jawa yang menjadi gambaran daya rusakindustrialisasi raksasa yang diawali oleh jalan raya pos. Sebuahkreatifitas kapitalistik demi profit margin yang tinggi, dan hargasebuah kesempatan mengembangkan emporium gula dan kopi terbesar didunia.
Perubahan Ekologik Perubahan ekologik terbesar yang dipicu oleh industrialisasi
perkebunan adalah deforestrasi. Tahun 1830 adalah titik awal turunnyaperubahan ekologik yang paling menonjol dalam hampir dua abad.
Grafik laju penurunan tegakan hutan dalam kurun 1 abad (Whitten, hal331)
Sebelum era tanam paksa, penggunaan kayu dalam jumlah besaradalah untuk membangun kapalkapal Belanda. Tanam paksa mendorongpetani memperluas lahan pertaniannya untuk menanam tanamanperdagangan. Kopi, cengkeh, dan teh adalah tanamantanaman umurpanjang yang merubah pemandangan hutanhutan di Jawa (Whitten, 1996).Meski pada awalnya tanam paksa hanya mewajibkan sedikit (5%) lahanpetani untuk ditanami tanaman komoditi, pada prakteknya petaniterpaksa menggarap tanah lebih luas lagi.
Sistem tumpang sari yang dianjurkan Pemerintah Hindia Belandahanya bisa diperlakukan pada tanaman tertentu seperti nila, tebu, dantembakau di arealareal pesawahan. Tetapi komoditi lain yang jadiandalan seperti kopi dan teh, mengharuskan para petani membongkarhutan dan menggantinya menjadi tanaman kopi dan teh. Dampaknyasungguh luar biasa. Dalam waktu singkat seluruh pegunungan di Jawadari ketinggian 600 hingga 1000 meter menjadi sabuk kopi,menghilangkan ekosistem hutan selamalamanya (Heffner, 1990).
Dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun, sejak tahun 18981922hutan yang hilang mencapai 22.000 km2 (atau 220,000 hektar) (Whitten:1996). Sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan kereta apimengikuti jalan raya pos. Sementara itu sejak tahun 1830an hingga1900 hutan yag hilang sudah mencapai 5 juta hektar. Hingga tahun 1973saja, hutan alam di Jawa hanya tinggal 11% (Donner: 1987).
Kopi dan teh adalah tanaman utama yang mengganti vegetasi hutan.Percepatan perluasan perkebunan kopi terjadi pada kurun waktu 18301833. Pada tahun 1833 saja, jumlah pohon kopi di seluruh Jawamencapai 116 juta pohon. Dua pertiga wajib tanam kopi berada diCirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Burger: 1962). Jika 1 pohonkopi membutuhkan luas lahan 4 meter persegi saja, maka luas lahankopi pada tahun 1833 sudah mencapai 464 ribu hektar berkontribusihampir 10% terhadap hilangnya hutan alam selama 70 tahun.
Salah satu kejadian yang berdampak fatal dari perluasan tanamankopi terjadi di Gunung Sewu, pesisir selatan Jawa. Pada tahun 1850Belanda mencoba menanam kopi di Gunung Sewu. Saat itu Belanda hutanalami di tempat tersebut adalah tanah aluvial yang subur dan cocokuntuk tanaman kopi. Belanda mengganti sebagian besar vegetasi diwilayah tersebut dengan tanaman kopi. Tapi kenyataannya wilayahtersebut adalah wilayah yang tidak cocok untuk tanaman kopi. Vegetasihutan di Gunung Sewu yang merupakan pegunungan kapur dan juga wilayahkarst tidak dapat tergantikan oleh tanaman lain, seperti kopi. Upayapenanaman ribuan pohon kopi gagal dan ditinggalkan begitu saja.Hilangnya vegetasi hutan oleh kegagalan kopi adalah kekeringan diwilayah yang berlangsung hingga 1,5 abad.
Perluasan wilayah perkebunan juga disokong oleh peralihanperalihan kuasa atas lahan. Pada jaman liberalisasi industri paskatanam paksa, sejumlah besar lahan diserahkan pada perkebunanperkebunan privat. Hasilnya, pada 18601870an, Belanda telahmenganugerahkan hak guna kepada hanya 345 orang untuk lahan seluas 1juta hektar di Jawa (Donner, 1987).
Pengubah ekologi Jawa yang lain adalah perkebunanperkebunantebu dan nila yang dikembangkan di daerah lahan basah di sepanjangpantai utara dan dataran di pedalaman seperti di Madiun, daerahdaerah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Burger mencatatpengembangan daerah tebu mencapai lebih dari 141 ribu bau.
Tabel: Luas Tanaman Tebu di Pulau Jawa 1833 – 1910 (bau)Karesidenan 1833 1860 1910Banten 2254Cirebon 1460 4200 15000Pekalongan 777 1500 3500Tegal 560 3200 10.000Semarang 543 1800 3300Jepara 5118 3700 8800Rembang 1221 Banyumas 300 5000Madiun 3512 800 6400Kediri 642 1900 20.000Surabaya 4424 8600 36.000Pasuruan 8361 6000 13.000Probolinggo 4700 13.000Besuki 3.850 2000 7000BanyuwangiJumlah Jawa 33.722 38.100 141.300sumber: Burger, 1962
Cerita tebu di Jawa adalah salah satu cerita paling mengharubiru dalam sejarah Jawa. Hingga awal abad ke 20, Jawa adalah
penghasil tebu terbesar di dunia dan memberi keuntungan luar biasabagi Kerajaan Belanda.
Perluasan infrastruktur dan migrasiDemi mempercepat mengalirnya barang dari wilayah produksi ke
pelabuhanpelabuhan dagang, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya,infrastruktur jalan raya di perluas. Jaringan Jalan yang bertulangbelakang Jalan Raya Pos yang sudah menghubungkan pelabuhanpelabuhandan beberapa wilayah produksi di Priangan dan Pantai Utara Jawadiperluas hingga ke pegunungan penghasil kopi dan teh.
Sejumlah bendungan dan irigasi dibangun terutama di wilayahwilayah penghasil tebu. Pelabuhanpelabuhan diperluas dan kotakotaberdiri dengan cepat seiring dengan peningkatan produksi ekspor.
Perluasan jalan mempercepat perpindahan penduduk ke wilayahwilayah yang dahulunya terisolasi seperti pegunungan Tengger. Jalanraya ke pedalaman mempercepat arus perpindahan manusia yangmenghindari tanam paksa tebu ke wilayahwilayah pegunungan.
Perpindahan penduduk selain didorong oleh peperangan, umumnyapetanipetani menghindari tanam paksa tebu karena waktu dan tenagayang diperlukan sejak tanam hingga panen luar biasa besardibandingkan menanam padi yang bisa dimakan atau kopi. Kopi tidakmembutuhkan kerja yang banyak terutama setelah masa tanam. Karena itubanyak petani dataran pergi ke daerah pegunungan menjadi petani kopimenghindari kerja berat di perkebunan tebu di dataran.
Akibatnya tekanan terhadap ekosistem pegunungan meningkat pesat.Di wilayah Tengger, jumlah penduduk meningkat lebih dari 20 kalilipat dalam 1 abad. Pada tahun 1830 penduduk Tengger berjumlah 2200an orang dan menjadi 49 ribu orang pada tahun 1930. Pertumubuhantercepat terjadi pada kurun waktu 1830 hingga 1870.
Sebelum industrialisasi paksa ada, pergiliran kerja diperkebunan atau di pabrik tidak pernah ada. Tetapi tanam paksamengharuskan kepalakepala desa mengatur waktu penduduk sedemikianrupa termasuk membebaskan penduduk dari kerja sosial desa jikamendapat kewajiban kerja di pabrik. Orangorang kaya membayar oranglain untuk melakukan kerja wajib dan ini terus berlangsung darisebuah adaptasi menjadi permanen.
Perluasan tanaman tebu dan nila (indigo) di dataran sungguhberdampak pada kehidupan rakyat di daearah dataran. Demi memenuhipasokan kepada pabrikpabrik gula, para petani yang terkena kerjapaksa terpaksa menghabiskan waktunya hanya untuk tebu dan nila.Organisasi sosial di pedesaan pun terpaksa berubah demi memenuhipasokan tenaga kerja untuk pabrikpabrik maupun perkebunan.
Tahun 1841, sekitar 2000 orang pindah dari daerah Bagelen karenatidak lagi kuat menanggung beban kerja yang begitu berat. Dibutuhkanwaktu lebih dari 9 tahun untuk mengupayakan agar jumlah pendudukkembali meningkat di wilayah tersebut (Burger, 1962).
Perluasan industri mendorong kelaparanDi sepanjang abad ke 19, berdasarkan analisa Boomgard (2002),
Jawa mengalami sejumlah pemburukan yang merupakan gabungan antarakekacauan iklim dan faktorfaktor ekonomipolitik. Periodeperiodetersebut adalah 1816 hingga 1824, kemudian 1844 hingga 1854, dan18621870.
Tahun 1816 hingga 1824 dipenuhi oleh kejadiankejadian kelaparanskala besar yang menimba Lombok, Bali dan Jawa. Setidaknya terdapatdua tahun yang sangat kering dan dua tahun yang sangat basah yangtidak menguntungkan bagi usaha pertanian. Iklim yang berubah yangdiduga disebabkan oleh letusan G. Tambora, menyebabkan gagal panen disejumlah besar wilayah.
Pengembangan jalan raya Pos 18081811 mengakibatkan rakyat pulauJawa mengalami penurunan kemampuan dalam bertahan hidup. Raffles danVan der Cappellen hadir di Jawa menggantikan Daendels. Keduanyamembawa nafas liberalisasi dan berupaya secara sungguh menerapkansistem yang berlaku pada kerajaankerajaan Eropa di Pulau Jawa.Struktur kerja feodalistik yang digunakan oleh VOC maupundimanfaatkan oleh Daendels hendak dihapuskan. Seluruh tanah diambilalih oleh kerajaan induk (Inggris di jaman Raffles, dan Belanda diJaman Vander Cappelen).
Pada saat ini pula sebuah sistem baru bernama pajak tanah danpajak kepala diperkenalkan. Dahulu, setidaknya hingga Daendels tiba,para raja maupun bupati memiliki wewenang atas tanah dan tenagakerja. Para raja atau bupati memungut upeti dari rakyat yang kemudiandijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Ketika VOCdibubarkan sistem ini masih berlanjut.
Seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropa, Daendels dan parapenerusnya menganggap hubungan feodalistik yang masih ada di PulauJawa menghambat industrialisasi. Bisnis dan pemerintahan harusdipisahkan, orang perlu diberikan kebebasan memiliki alat produksidemikian pula tenaga kerja bebas. Negara (dalam hal ini Hindia Timur)mendapat pemasukan dari pajak dan sewa tanah. Namun untuk itukekuatankekuatan feodal harus dihilangkan. Hubungan mereka denganhambahambanya harus diputus sehingga perbudakan menjadi hilang danrakyat menjadi tenaga kerja bebas atau menyewa tanah untukberproduksi.
Raffles dan Van der Cappellen memberlakukan pajak agar HindiaTimur mendapatkan pemasukan. Rakyat dibebani pajak dan sewa tanahjika mereka menggarap lahan bahkan untuk hidup subsisten.
Akibatnya, rakyat berproduksi matimatian tetapi hanya itumembayar pajak. Sejumlah catatan tentang ekonomi abad ke 19menunjukkan bahwa pendapatan rakyat yang baru berkenalan denganekonomi uang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kolonial Rafflesmaupun Van der Cappelen. Jika tidak, tanah atau aset mereka akandisita oleh pemerintah kolonial.
Kondisi perekonomian yang belum membaik sehabis perang Eropa danpembangunan Jalan Raya Pos, ditambah iklim yang buruk, membuat rakyatterpaksa menjual seluruh hasil panen yang tidak seberapa demimembayar pajak. Kadangkala tidak ada lagi uang tersisa untuk membelimakan. Kehidupan subsisten pun semakin sulit akibat pembayaran pajak.Maka tak heran jika pada jaman percobaan liberalisasi Raffles dan Vander Cappellen kelaparan melanda di beberapa bagian Pulau Jawa.
Pada episode yang lain, di jaman tanam paksa, kelaparan jugamasih melanda beberapa bagian Pulau Jawa. Kali ini, kisahnya bukandiakibatkan oleh produksi yang harus dijual sepenuhnya demi membayarpajak. Kelaparan di jaman tanam paksa muncul akibat laju produksiberas yang terhambat karena didesak oleh perluasan tanaman tebu.
Kerja yang demikian berat plus pengerahan tenaga kerja yangbesar di perkebunan tebu dan nila mengakibatkan petani tidak menguruspadi lagi. Seluruh tenaga dan waktu tercurah untuk tanamanperdagangan. Akibatnya panen padi menyusut dan kekurangan pangantejadi.
Kondisi kelaparan di jaman tanam paksa berbeda dengan jamanliberalisme cobacoba ala Raffles dan Van der Cappellen. Di jamantanam paksa menurunnya produksi beras relatif dibanding denganproduksi gula dan pertumbuhan penduduk menghasilkan kelangkaan beras.Harga beras dan bahan pangan lainnya naik akibat produksi yang tidakmemadai.
Rakyat yang mendapat upah dari perkebunanperkebunan partikelirtidak sanggup lagi membeli beras. Demikian pula subsistensi yangpudar akibat pengerahan tenaga kerja untuk menanam tebu dan tanamankomoditi lainnya.
Masalah lain yang dihadapi industri PamanukanCiasem adalahlahan tebu, karena kebunkebun tebu yang dibuka tidak diletakkandi sawah, tetapi dilakukan pembukaan tanah yang sama sekalibaru, maka diperlukan ketekunan tersendiri untuk menyiapkantanah darat menjadi tanah sawah. Padahal, tebu adalah tanamanmanja yang menuntut irigasi dan drainasi intensif. (Cahyono,1988)
Sejumlah wilayah yang dahulunya mampu mengekspor beras kewilayah lain bahkan keluar Jawa menyusut kemampuannya. Bahkan, panenpadi di jaman tanam paksa untuk beberapa daerah tidak lagi mampumemenuhi kebutuhan wilayah setempat. PamanukanCiasem, Cirebon,Banyumas, Bagelen, dan Bojonegoro adalah wilayah yang mengalamikelaparan di abad ke 19.
Di wilayah Bagelen, tanah menjadi tidak subur akibat tanamannila. Padi tidak lagi tumbuh subur jika sawah sebelumnya ditanaminila. Petani menjadi frustasi dan meninggalkan desadesa bukan hanyakerja yang berat tetapi karena rusaknya kesuburan tanah akibattanaman perdagangan.
Mundurnya sektor pertanian padi diakibatkan bukan hanya karenalahanlahan basah dikembangkan untuk tebu dan nila, terutama tebu,tetapi juga air. Irigasi yang dikembangkan oleh pemerintah HindiaBelanda tidak lagi diperuntukkan untuk mendukung tanaman padi, tetapitebu.
Setelah dihajar oleh kelaparan, Jawa masih harus pula diderabencana lain, penyakit. Boomgard (2002) mencatat munculnya wabahcacar, kolera, dan demam typus di sebagian besar pulau Jawa terutamadi daerahdaerah yang mengalami minus pangan. Sayangnya, tim penulisbelum menemukan catatan seberapa besar korban jatuh akibat wabahpenyakit ini dan bagaimana wabah berkaitan dengan runtuhnya kemampuansubsistensi rakyat pada jaman itu.
Bagaimana rakyat yang masih bertahan dapat selamat dan keluardari situasi ini? Migrasi adalah salah satunya. Meski beberapawilayah mengalami pemburukan situasi akibat tanam paksa, tetapibeberapa wilayah lain tidak mengalami kondisi pemburukan yang cukupserius. Wilayah Surabaya, Probolinggo, dan Pasuruan yang merupakanprodusen gula terbesar di Pulau Jawa saat itu menjadi salah satusasaran migrasi.
Burger dan Atmosudirjo (1962) menulis bahwa salah satu akibattanam paksa adalah munculnya tenaga kerja bebas. Rakyat yang tidakmemiliki tanah atau lari dari kewajiban tanam paksa memilih menjadipekerja upahan di perkebunanperkebunan partikelir. Mereka mengembaradi wilayahwilayah perkebunan dan seringkali terlibat masalahmasalahpelanggaran hukum. Sebagai pekerja upahan bebas, golongan inimenghidupi sektorsektor 'penghibur' yaitu perjudian, candu, danronggeng. Bandarbandar judi dan candu serta para penari ronggenghidup dari uang para pekerja bebas ini.
1. Jawa pada Akhirnya
Hingga abad ke 21, watak perusakan alam lewat mega proyek yangberujung pada, penggusuran masif, pemindahan paksa, kerusakan siklusalam yang menerus, yang menghasilkan korban manusia yang terusmenerus hidup dalam kondisi survival tetap terus berjalan terusmenerus ada. Migrasi ke perkotaan adalah fenomena yang tak tertanganidari jaman ke jaman. Tumbuhnya mukim kumuh di perkotaan, turunnyaderajat kesehatan di banyak wilayah adalah fenomena yang telahberlangsung di abad sebelumnya. Meluasnya wilayah yang semakin rentanterhadap bencana merupakan indikasi model pembangunan seperti yangdimimpikan oleh Daendels dan diikuti oleh para penggantinya, baik dimasa kolonial maupun republik gagal mewujudkan mimpi kemakmuran bagimayoritas penduduk Jawa.
Jawa adalah potret konkret bagaimana sebuah watak kreatif namundestruktif selalu menggunakan rumus yang sama dalam menentukan siapayang mendapat untung dan mengabaikan tumbuhnya korban manusia danalam yang berjumlah besar. Lebih jauh lagi umpan balik dari model
pembangunan yang disokong infrastruktur raksasa pada waktunyamenghasilkan perluasan krisis yang dijawab dengan rumus yang samapula. Perbaikan atau penambalan skala raksasa, dengan tujuan yangseolaholah mulia, namun tetap hanya memberikan keuntungan padasegelintir orang dan menyengsarakan orang lain.
Pertanyaannya adalah, bagaimana warga Jawa beserta parapemimpinnya bisa memutus lingkaran setan watak, mimpi, dan praktekDaendelis.
Daftar Pustaka
Boomgard, Pieter, “The development of colonial health care in Java;An exploratory introduction” dalam “: Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 149 (1993), no: 1, Leiden, 77-93, www.kitlv-journals.nl
Burger,D.H, dan Atmosoedirjo, Prajudi, “Sejarah Ekonomis SosiologisIndonesia: Jilid Pertama”, Pradnya Paramitra. Jakarta. 1962
Cahyono, Edi, “Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuurstelsel:
Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula”, Skripsi Jurusan Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1988.http://members.fortunecity.com/edicahy/thesis/index.html
Day, Clive,” The Policy and Administration of the Dutch in Java”,Oxford University Press.Kuala Lumpur 1972.
De Graaf, H.J and Pigeaud, TH.G, “Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa:Peralihan dari Majapahit ke Mataram”, Grafittipers dan KITLV, 1974.
de Vries, Egbert, “Pertanian dan Kemiskinan di Jawa”, Yayasan OborIndonesia, Jakarta, 1985.
Diamond, Jarred,”Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive”,Penguin Group,New York. 2005.
Donner, Wolf, “Land Use and Environment in Indonesia”, C. Hurst &Co.Ltd, 1987.
Frederick, William H. and Worden, Robert L. editors. “Indonesia: ACountry Study”. Washington: GPO for the Library of Congress, 1993.
Heffner, Robert. W, “Geger Tengger: Perubahan Sosial dan PerkelahianPolitik”, LkiS, Yogyakarta, 1999.
Moertono, Soemarsaid,”Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa MasaLampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX”, YayasanObor Indonesia, Jakarta, 1985.
Pelluso, Nancy. “Rich Forest Poor People: Resource Control andResistance in Java”, University of California Press, Berkeley, 1992.
Penders, C.L.M, “Bojonegoro 1900-1942, A story of Endemic Poverty inNorth-East Java- Indonesia”, Gunung Agung, Singapore, 1984.
Penders, C.L.M.editors, “Indonesia: Selected Documents on Colonialism1830-1942”, University of Queensland Press, 1977.
Pratiwo, Nas. P “Java and de Groote Postweg, La Grande Route, theGreat Mail Road, Jalan Raya Pos” in “Bijdragen tot de Taal-, Land- enVolkenkunde, On the road The social impact of new roads in SoutheastAsia 158 (2002), no: 4, Leiden, 707-725”, www.kitlv-journals.nl
Purwanto, Bambang, “Peasant Economy and Institutional Changes in LateColonial Indonesia”, Paper presented to the International Conferenceon Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th
and 20th Centuries h, Amsterdam 25-26 February 2002. www.iisg.nl.
Raffles, Thomas. S. “The History of Java: Vol I and II,” OxfordUniversity Press, Kuala Lumpur, 1978.
Stockdale, John Joseph, “Island of Java”, Periplus, Singapore. 2003.
Toer, Pramoedya Ananta.” Jalan Raya Pos”, Hasta Mitra, 2003.
Van Niel, Robert. “Sistem Tanam Paksa di Jawa”, LP3ES, Jakarta, 2003.
Whitten, Tony. Soeriatmadja and Affif, Suraya, “ The Ecology of Javaand Bali”, Periplus, Singapore. 2000.