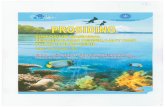Pseudogenes contribute to the extreme diversity of nuclear ribosomal DNA in the hard coral Acropora
Ekosistem Terumbu karang dan Transplantasi Karang (Acropora formosa)
Transcript of Ekosistem Terumbu karang dan Transplantasi Karang (Acropora formosa)
Ekosistem Terumbu Karang (Acropora Formosa) untukTransplantasi Karang (Coral transplantation)
Oleh: Sukarmin IdrusUniversitas Khairun Ternate
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan2013
Ekosistem Terumbu KarangKarang atau disebut polip memiliki bagian-bagian tubuh
terdiri dari mulut yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsiuntuk menangkap mangsa dari perairan serta sebagai alatpertahanan diri, rongga tubuh (coelenteron) yang juga merupakansaluran pencernaan (gastrovascular), dua lapisan tubuh yaituektodermis dan endodermis yang lebih umum disebut gastrodermiskarena berbatasan dengan saluran pencernaan (Gambar di bawahini). Bertempat di gastrodermis, hidup zooxanthellae yaitu algauniseluler dari kelompok Dinoflagelata, dengan warna coklat ataucoklat kekuning-kuningan (Timotius, 2003).
Gambar . Anatomi Karang (Sumber; Ahmad 2007)Menurut Veron (1995) dalam Wikipedia (2009) terumbu karang
merupakan endapan massif (deposit) padat kalsium (CaCo3) yangdihasilkan oleh karang dengan sedikit tambahan dari alga
berkapur (Calcareous algae) dan organisme -organisme lain yangmensekresikan kalsium karbonat (CaCo3). Dalam proses pembentukanterumbu karang maka karang batu (Scleractina) merupakan penyusunyang paling penting atau hewan karang pembangun terumbu (reef -building corals). Karang batu termasuk ke dalam Kelas Anthozoa yaituanggota Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip.Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua Subkelas yaituHexacorallia (Zoantharia) dan Octocorallia, yang keduanyadibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologi.
Hewan karang sebagai pembangun utama terumbu adalahorganisme laut yang efisien karena mampu tumbuh subur dalamlingkungan sedikit nutrien (oligotrofik). Menurut Sumich (1992)dan Burke et al. (2002) dalam Wikipedia (2009) sebagian besarspesies karang melakukan simbiosis dengan alga simbiotik yaituzooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis,zooxanthellae menghasilkan oksigen dan senyawa organik melaluifotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karangmenghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfat dan karbondioksida untuk keperluan hidup zooxanthellae.
Selanjutnya Sumich (1992) dalam Wikipedia (2009) menjelaskanbahwa adanya proses fotosintesa oleh alga menyebabkanbertambahnya produksi kalsium karbonat dengan menghilangkankarbon dioksida dan merangsang reaksi kimia sebagai berikut:
Ca (HCO3) CaCO3 + H2CO3 H2O + CO2
Fotosintesa oleh algae yang bersimbiose membuat karang pembentukterumbu menghasilkan deposist cangkang yang terbuat dari kalsiumkarbonat, kira-kira 10 kali lebih cepat daripada karang yangtidak membentuk terumbu (ahermatipik) dan tidak bersimbiosedengan zooxanthellae.
Klasifikasi Karang Acropora formosaDalam Klasifikasi dunia Hewan, Karang Termasuk Dalam Kelas
Anthozoa (suatu kelas dalam filum colenterata). Secara garis besarVeron (1986) dalam Yusuf (2005) Mengklasifikasikan karangAcropora formosa sebagai berikut :
Filum : Colenterata/CnidariaKelas : AnthozoaOrdo : ScleractiniaFamili : Acroporidae
Genus : Acropora spSpesies : Acropora formosa
Gambar Koloni karang Acropora formosaMorfologi Karang Acropora formosa
Marga Acropora mempunyai bentuk percabangan sangatbervariasi dari karimboba, aborsen, kapitosa dan lain-lain. Cirikhas dari marga ini adalah mempunyai axial koralit dan radial koralit.Bentuk koralit juga bervariasi dari bentuk tubular, harifon dantenggelam.
Acropora formosa mempunyai bentuk percabangan aborsen denganpercabangan rampai sampai gemuk. Radial koralit membentuk tabungdengan bukan membulat atau oval tersusun merata dan rapat. Warnakoloni kecoklatan dengan unjung cenderung memutih. Terbesar diseluruh perairan Indonesia (Wells, 1995) dalam (Suharsono, 1996).
Terumbu karang di daerah tropis secara fisik didominasioleh organisme yang hidupnya menetap dalam jangka waktu yangpanjang. Karang Scelractinia yang umumnya yang hidup secaraberkoloni dan memiliki alga filamen (zooxanthellae) yang hidup padajaringan tubuhnya, memiliki banyak bentuk mulai dari tegakseperti pohon, tabel ataupun semak hingga bentuk yang tidak tegakseperti kerak ataupun piringan. Ukuran maksimum, lajupertumbuhan, laju produksi serta kisan habitat yang didiamisangat berbeda tiap spesiesnya (Tomascik, 1991) dalam (Yusuf,2005).
Karang Acropora berbeda dari yang lainnya dalam hal dua tipepolip yang di milikinya. Polip bagian tengah atau bagian aksialmelintasi bagian tengah dari sebuah cabang dan membuka padaunjungnya. Pada saat ujung cabang tersebut tumbuh maka akanmembentuk pucuk dengan sejumla polip jenis lainnya disebut polip
radial. Percabangan selanjutnya terjadi pada saat sebuah koralitradial berubah menjadi sebuah koralit aksial dan mulai memanjangdan membentuk pucuk. Tipe perubahan ini memungkinkanterbentuknya sejumlah besar bentukan sehinga karang Acroporadapat terlihat menyerupai pohon, semak, tabel, pelat dan berbagaibentuk lainnya. Hal ini juga memungkinkan karang genus ini untuktumbuh cepat dan mengisi tempat pada terumbu, baik di atas maupundi bawah karang lainnya.
Pertumbuhan karang batu (sleractinia) dalam hal ini genusAcropora Spesies dari Acropora formosa lebih cepat pertumbuhannyadibandingkan dengan jenis karang batu lainnya hal ini disebabkankarena bentuk pertumbuhan karang ini adalah bercabang (branching)sehingga proses kalsifikasi yang terjadi lebih cepat. Sedangkanjenis karang yang bentuk pertumbuhannya seperti otak (masif)pertumbuhannya sangat lambat karena memerlukan kalsium karbonat(CaCO3) yang banyak sehinga proses kalsifikasi yang ada berjalansangat lambat. Parameter Lingkungan
Pertumbuhan karang dan penyebaran terumbu karang tergantungpada kondisi lingkungannya, Dahuri dkk, (2004). Kondisi inipada kenyataannya tidak selalu tetap tetapi seringkali berubahkarena adanya gangguan baik yang berasal dari alam atau aktifitasmanusia. Faktor kimia dan fisik yang diketahui dapat mempengaruhipertumbuhan karang antara lain cahaya matahari. suhu, salinitasdan sedimen, sedangkan faktor biologis biasanya berupa predatoratau pemangsa (Supriharyono, 2000).Cahaya
Sinar matahari merupakan hal yang sangat penting dalammelengkapi cahaya yang di butuhkan oleh tumbuhan untuk prosesfotosintesis. Tumbuhan tidak dapat hidup terus tanpa adanyacahaya matahari yang cukup, sehingga penyabarannya di batasi padadaerah kedalaman dimana cahaya matahari masi dapat dijumpai.Penyinaran matahari akan berkurang secara cepat sesuai denganmakin tinggi kedalaman laut (Hutabarat dan Evans, 1984).
Karang hermatipik membutuhkan cahaya yang cukup untukkegiatan fotosintesa dari alga yang berada dalam jaringannya.Dalamnya penetrasi cahaya yang menentukan jangkauan kedalamanyang dapat dihuni oleh karang hermatipik (Lalamentik, 1991).
Berkaitan dengan pengaruh cahaya terhadap karang, makafaktor kedalaman juga membatasi kehidupan binatang karang. Padaperairan yang jernih mungkin penetrasi cahaya bisa sampai padalapisan yang sangat dalam, namum secara umum karang tumbuh lebihbaik pada kedalaman kurang dari 20 m (Kinsman, 1964 dalamsupriharyono, 2000).Suhu
Pada permukaan laut, air murni berada dalam kedalaman cairpada suhu tertinggi 100ºC dan suhu terendah 0ºC. karena adanyasalinitas dan densitas maka air laut dapat cair pada suhu dibawah0ºC. Suhu air laut berkisar antara suhu dibawah 0ºC sampai 33ºC.Perubahan suhu dapat berpengaruh kepada sifat-sifat laut lainnyadan kepada biota laut (Romimohtarto dan Juwana, 2001).Selanjutnya Nontji (2002) menyatakan bahwa hewan laut hidup dalambatas-batas suhu yang tertentu, ada yang mempunyai toleransi yangbesar terhadap perubahan suhu, sebaliknya adapula yang mempunyaitoleransi kecil.
Suhu merupakan faktor penting yang menetukan kehidupankarang, Supriharyono (2000), selanjutnya ditambahkan oleh Wells(1959) dalam Supriharyono (2000) bahwa suhu yang baik untukpertumbuhan karang adalah berkisar antara 25-29ºC, denganperkembangan paling optimal pada perairan yang memiliki rata-ratasuhu tahunannya antara 23 - 25ºC (Tomascik, 1991 dalam Yusuf2005).Salinitas
Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungangaram dari suatu perairan, yang dinyatakan dalam permil (‰).Kisaran salinitas air laut berada antara 0 – 40 g/kg air laut.Secara umum, salinitas permukaan perairan Indonesia rata - rataberkisar antara 32 – 34 ‰ (Dahuri dkk, 2004).
Nybaken (1988) menyatakan bahwa karang hermatipik adalahorganisme lautan yang tidak dapat bertahan pada salinitas yangmenyimpang dan salinitas yang normal yaitu 32 – 35 ‰ (Nybaken,1988).Arus
Arus merupakan gerakan air yang sangat luas terjadi padaseluruh dunia, Hutubarat dan Evans (1984). Kemudian Nontji (2002)menyatakan bahwa arus merupakan gerakan mengalir suatu masa airyang dapat disebabkan oleh tiupan angin, atau karena perbedaan
densitas air laut atau pula dapat di sebabkan oleh gerakangelombang panjang.
Karang Acropora menurut Bengen (1995) tergolong sensitivekarena membutuhkan kecerahan perairan yang tinggi dan perairanterbuka dengan sirkulasi air yang bebas. Karakteristik lingkunganseperti ini diperlukan karena tipe karang ini tidak dapatmembersikan diri sendiri sebab memiliki polip yang relatif kecilsehingga memerlukan ombak dan arus yang sesuai. Smith (1992)dalam Lalamentik (1991) menambahkan bahwa semakin cepat arusdapat membantu karang dalam menghalau sedimen yang terjadi dalamproses pembersihan diri.Sedimentasi
Sedimentasi merupakan masalah yang umum di daerah tropis,pembangunan di daerah pantai dan aktifitas manusia sepertipengerukan dan pembukaan hutan menyebabkan pembebasan sedimen keperairan pantai atau ke daerah terumbu karang (Supriharyono,2000). Selanjutnya Abdullohmukhtar (2011) menyatakan bahwapertumbuhan karang, seperti di Pantai Bandengan, Jepara, JawaTengah, lambat pada musim hujan karena banyaknya sedimen.Sebaliknya cepat pada musim kemarau. Sebagai contoh, pertumbuhanAcropora aspera hanya sekitar 1-2 mm/bulan pada musim hujan,sedangkan pada musim kemarau mencapai > 10 mm/bulan.
Menurut Dahuri dkk, (2001) sedimentasi dapat menyebabkankematian pada karang baik secara langsung maupun tidak langsung.Sedimentasi yang dapat langsung mematikan binatang karangmempunyai ukuran yang besar atau banyak sehingga dapat menutupipolib karang (Hubbard dan Pocock, 1972; (bak dan Elgersuizen,1976) dalam Supriharyono, 2000). Sedangkan pengaruh tidaklangsung adalah terjadinya penurunan penetrasi cahaya matahariyang penting untuk fotosintesis alga simbion atau zooxanthellae, danbanyaknya energi yang dikeluarkan untuk menghalau sedimen yangberakibat turunnya laju pertumbuhan karang (Pastorok dan Bilyard,1985 dalam Supriharyono, 2000).
Menurut Pastrook dan Bilyard, 1985; dalam Supriharyono,2000, menyatakan bahwa laju sedimentasi antara 1-10 gr dalamkategori kecil-sedang, pada 10-50 dalam kategori sedang-bahayadan pada kategori bahaya-katastropik mencapai < 50. SelanjutnyaLalamentik (1991) menyatakan bahwa banyak tipe sedimen yangmuncul pada dan sekitar terumbu karang, termasuk didalamnya
hancuran karang yang kasar, berbagai tipe pasir dan lumpur yanghalus.Pertumbuhan Karang Transplantasi
Seperti hewan lain, karang memiliki kemampuan reproduksisecara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual adalahreproduksi yang tidak melibatkan peleburan gamet jantan (sperma)dan gamet betina (ovum). Pada reproduksi ini, polip/kolonikarang membentuk polip/koloni baru melalui pemisahan potongan-potongan tubuh atau rangka. Ada pertumbuhan koloni dan adapembentukan koloni baru sedangkan reproduksi seksual adalahreproduksi yang melibatkan peleburan sperma dan ovum (fertilisasi).Sifat reproduksi ini lebih komplek karena selain terjadifertilisasi, juga melalui sejumlah tahap lanjutan (pembentukanlarva, penempelan baru kemudian pertumbuhan dan pematangan)(Timotius, 2003).
Salah satu perbandingan reproduksi aseksual dan seksualdipandang dari sisi ketahanan dan adaptasi terhadap lingkunganadalah waktu pembentukan anakan, untuk reproduksi aseksual karangmembutuhkan waktu yang singkat untuk tumbuh sedangkan untukreproduksi seksual karang membutuhkan waktu dan proses lebihpanjang untuk pertumbuhan, ini dikarenakan karena pada reprodusiaseksual karang dibentuk oleh potongan atau rangka dari indukkarang sedangkan pada reproduksi seksual tidak (Timotius, 2003).
Koloni karang hermatiphik mengandung alga (zooxanthellae) yanghidup bersimbiosis dengan terumbu karang. Zooxanthellae yang dikoloni karang membentuk bangunan karang. Gereau dan Gereau (1959)dalam Supriharyono (2000) menyatakan bahwa merupakan factor yangesensial dalam proses klasifikasi atau produksi kapur bagihermathipic corals atau reef building corals. Pertumbuhan setiap spesieskarang berbeda. Spesies tertentu mempunyai pertumbuhan yangsangat cepat, yaitu bias mencapai 2 cm/bulan (karang bercabang)tetapi ada pula yang mempunyai pertumbuhan sangat lambat yaitu 1cm/tahun. Menurut defenisi pertumbuhan karang merupakanpetambahan panjang linear, berat, volume, atau luas kerangkaatau bangunan kapur (Calsium) spesies karang dalam kurun waktutertentu (Budemeier dan Tinzie, 1962 dalam Supriharyono, 2000).
Kecepatan tumbuhan karang juga ditentukan oleh kondisilingkungan dimana hewan ini berada. Perairan yang kondisilingkungannya mendukung pertumbuhan karang, maka karang tumbuh
lebih cepat di bandingkan dengan daerah yang lingkungannyatercemar (Supriharyono, 2000).
Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2007)karang dari genus Acropora sp memiliki pertumbuhan pada umur 3 –6 bulan. Dipilihnya genus Acropora formosa sebagai bahan penelitiandalam transplantasi karang karena, jenis karang ini memiliki awalpertumbuhan, memiliki kisaran pertumbuhan yang cepat sertamemiliki ketahanan hidup yang besar. Deslina (2004) kisaranpertambahan panjang genus Acropora formosa adalah 1.20 cm selama 2bulan, dan menurut Sadarun, (1999) Genus Acropora formosa memilikiketahan hidup yang besar dari genus Acropora sp lainnya. GenusAcropora formasa juga mengalami Awal pertumbuhan yang cepat danpertambahan panjang lebih tinggi dibandingkan dengan genusAcropora sp lainnya (Ofri Johan dkk, 2008).
Besarnya ukuran fragmen transplantasi sangat menentukanpertumbuhan dan keberasilan dari transplantasi karang (Ofri Johandkk, 2008). Horriot dan Fisk (1988) dalam Ofri Johan dkk (2008)mengemukakan bahwa dalam transplantasi karang Acropra sp harusmemperhatikan ukuran karang tersebut, ukuran yang lebih kecilakan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Pertambahan panjangdipengaruhi oleh sifat biologi model percabangan karang sepertimodel karang branching arborescent cenderung mempunyaipertambahan panjang mengarah ke atas lebih besar (Sadarun, 1999).
Menurut Deslina (2004), Kisaran yang diperoleh padapertambahan karang Acropora sp selama 2 (dua) bulan pengamatanadalah 1,34 cm – 1,62 cm , yang ini berbeda dengan kisaran yangdiperoleh Sadarun (2000) dengan masa pengamatan 5 (lima) bulanberkisar antara 2,01 cm – 4,91 cm, sedangkan menurut Yahyah(2001) dengan masa pengamatan 6 (enam) bulan berkisar antara 1,49cm – 3,50 cm. Diduga adanya perbedaan kisaran ini karena pengaruhperairan dan periode waktu pengamatan. Ketahanan Hidup Karang Transplantasi
Data Ketahanan hidup atau keberhasilan hidup fragmen karangdihitung dengan menghitung jumlah fragmen karang yang masihberada di atas substrat transplantasi sampai akhir pengamatan.Penempelan fragmen pada substrat sangat dipengaruhi olehkecepatan karang membentuk rangka kapur baru setelah dipatahkandari induknya. Ketahanan hidup dikatakan mencapai 100% apabila
semua fragmen karang yang ditransplantasikan tidak terlepas darisubstratnya (Sadarun, 1999).
Tingkat ketahanan hidup fragmen karang transplantasi sangatditentukan oleh penempelan fragmen pada karang, sedimen danturbiditas, ukuran fragmen, gangguan dari spesies pengganggu(ikan, dan keong pemakan karang) serta banyaknya alga di suatuperairan. Amaryllia dkk (2003) menyatakan bahwa penempelanfragmen pada substrat sangat dipengaruhi oleh kecepatan karangmembentuk rangka kapur baru setelah dipatahkan dari induknya,setelah fragmen merekat pada substrat maka energi yang awalnyadigunakan untuk membentuk kerangka kapur baru (regenerasi)dialihkan untuk pertumbuhan dan memperbesar ukuran diametersehingga karang mencapai ukuran idealnya.
Dodge dan Vaysnis (1977) dalam Ofri Johan dkk (2008)mengemukakan bahwa sedimen dan turbiditas yang terus meningkatakan menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan dan meningkatkanangka kematian karang, Selanjutnya Bak dan Criens (1981) dalamOfri Johan dkk (2008) bahwa keberasilan hidup dari karangtransplantasi sangat ditentukan oleh ukuran fragmen karang.
Kematian dari fragmen karang juga ditentukan oleh hewanpemakan karang yang bersembunyi dan menempel di percabangankarang yang umumnya adalah jenis Drupella sp dari kelompok hewankekerangan. Selain itu kematian juga ditentukan oleh alga yangmenutupi fragmen karang sehingga terjadi perubahan warna menjadicoklat kehitaman (Ofri John dkk 2008), Seperti yang dikemukakanoleh Bak dan Criens (1981) dalam Ofri Johan dkk (2008) bahwakeberasilan hidup dari karang transplantasi juga di tentukan olehFilamentous algae (turf algae). banyak alga disuatu perairandisebabkan oleh kelimpahan nutrient yang dapat menyebabkanterganggunya proses klasifikasi, laju pertumbuhan, jumlahzooxantellae dan dan jumlah populasi karang (Hoegh dan Guldberg(1997) dalam Ofri Johan dkk (2008)).
Transplantasi Karang (Coral transplantation)Transplantasi karang (coral transplantation) adalah pencangkokan
atau pemotongan karang hidup untuk dicangkok di tempat lain ataudi tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan, bertujuanuntuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami.Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi
terumbu karang yang telah rusak, dan dapat pula dipakai untukmembangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada(Harriott, 1988 dalam Anonim, 2010).
Kegiatan transplantasi di Indonesia telah dilakukan di PulauPari Kepulauan Seribu dengan menggunakan substrat keramik, betondan gerabah. Tujuannya adalah untuk program percontohan dalammerehabilitasi pulau-pulau yang kondisi terumbu karangnya sudahrusak serta dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata laut, programpendidikan, penelitian dan uji coba dibidang perdagangan
Dimasa mendatang transplantasi karang akan memiliki banyakkegunaan antara lain: untuk melapisi bangunan-bangunan bawah lautsehingga lebih kokoh dan kuat untuk memadatkan spesies karangyang jarang atau terancam punah dan untuk kebutuhan pengambilankarang hidup bagi hiasan akuarium (Moka, 1995 dalam Anonim,2010).Teknik-Teknik Transplantasi Karang
Beberapa teknik untuk meletakan karang yang ditransplantasikan adalah semen, lem plastik, penjepit baja, dankabel listrik plastik. Dari beberapa percobaan yang telahdilakukan, ada beberapa kententuan untuk transplantasi karang,yaitu (Coremap & Yayasan Lara Link Makassar, 2006):
1. Untuk transplantasi karang diperlukan suatu wadah betonsebagai substrat dimana karang ditanam.
2. Jenis karang bercabang lebih cepat pertumbuhannya, dan mampumenyesuaikan dibandingkan karang masif.
3. Semua lokasi perairan pada dasarnya dapat dilakukantransplantasi dengan syarat kondisi hidrologik masih dalambatas toleransi pertumbuhan karang.
4. Hasil percobaan pada habitat yang berpasir tetapi dengankesuburan yang tinggi pertumbuhan karang lebih cepatdibandingkan pada daerah yang karannya rusak.
5. Wadah karang yang ditransplantasi sebaiknya tidakmenghalangi aerasi oleh arus.Menurut Anonim (2010), karang untuk transplantasi harus
diambil dari tempat yang sama dengan tempat pelaksanaantransplantasi terutama dalam hal pergerakan air, kedalaman danturbiditas. Transplantasi karang dalam koloni besar dapatdilakukan walaupun tanpa memerlukan perlekatan. Tingkat ketahananhidup karang yang ditransplantasi dapat tinggi walaupun tidak
dilekatkan pada substrat asal saja pelaksanaannya dilakukan didaerah terlindung terutama dari aksi gelombang. Untuk mengurangistres, karang yang akan ditransplantasi dilepaskan secara hati-hati dan ditempatkan dalam wadah plastic berlubang serta prosespengangkutan dilakukan di dalam air.
Contoh beberapa metode-metode transplantasi karang yangdapat digunakan dapat dilihat pada Gambar 3. Keunggulan danKelemahan dari masing-masing metode transplantasi karang dapatdilihat pada Tabel 1.
Gambar . Metode - metode transplantasi yang dapat digunakan
Sumber ; Anonim, 2010
Keterangan Gambar:1. Patok besi2. Karang bercabang3. Jaring4. Karang masif5. Substrat gerabah6. Karang Submasif7. Rangka Besi
a. Metode Patokb. Metode Jaringc. Metode Jaring dan
Substratd. Metode Jaring dan
Rangkae. Metode, Rangka dan
Substrat
Tabel Keunggulan dan Kelemahan Beberapa Metode Transplantasi Karang
MetodeTransplant
asi
Bahan dan CaraKerja
Keunggulan Kelemahan
a. Metode Patok
Patok kayu tahanair atau besiyang dicat antikarat ditancapkandi perairan
Biaya yangdibutuhkansangat sedikit,pemasanganrelative mudah.Gangguan sampahhampir tidakada. Cocokuntuk karanglunak,waktu/lamapekerjaanrelativesingkat
Tata letakmetode patokdidasarperairantidakteratur,karenasangattergantungdari kondisidasarperairan.Karang besidapatmenyebkanpencemaran
b. Metode Jaring
Jaring atauwaring bekas dan
Bahan mudadidapatkan,
Sulit untukdibersikan,
tali ris denganukurandisesuaikandengan kebutuhan
dapatmenggunakanbahan bekas,biaya lebihmurah, baikuntuk tiapkarang massif(bukanbercabang)
sukar dalampengukurangterutamauntukmengukurtinggi,pertumbuhankarang tidakrata,kedudukanmediadidasarperairankurangstabil
c. Metode Jaring dansubstrat
Jaring yangdilengkapi dengansubstrat yangterbuat darisemen, keramikatau gerabahdengan ukuran 10x 10 cm
Pengukuranrelative lebihmurah, lebihrapid danteratur, baikuntuk karangyang bercabang.
Biaya lebihmahal,prosespemasanganlebih rumit,membutuhkantenaga yanglebihbanyak,membutuhkanwaktu yanglebih lama
Lanjutan Tabel 1
MetodeTransplant
asi
Bahan dan CaraKerja
Keunggulan Kelemahan
d. Metode jaring danrangka
Rangka besi yangdicat anti karatdan diatasnyaditutupi denganjaring yang
Konstruksinyalebih kokohdaripada metode1,2 dan 3 dapatditata sesuai
Berbagaikarang yangberbentukbercabangtidak dapat
diikat secarakuat dan rapih.Rangka yang idealberukuran 100 x80 cm berbentukbujur sangkar danpada bagianujung-ujung bujursangkar, terdapatkaki-kaki tegaklurus masing-masing sepanjang10 cm, di bagianbujur sangkarnyaditutupi denganjaring tempatmengikat bibitbibittransplantasi
dengankeinginan,monitoring danevaluasi lebihmudah, baikbagi karangmassifbercabang,memiliki nilaiestetika.
tumbuhdengantegak, biayasedikitlebih mahal.Rangka besidapatmenyebabkanpencemaran
e. Metode Rangka danSubstrat
Metode inimerupakanperpaduan antarametode 3 dan 4.Ukuran diametersubstrat + 10 cmdengan tebal 2cm, panjang patok5-10cm, bahanpatok terbuatdari peralatankecil yang diisisemen dan dibericat agar tidakmengakibatkanpencemaran,rangka sebaiknyaberbentuk sikuberukuran 100 x80 cm dan dibericat agar tidakmengakibatkanpencemaran
Lebih koko dankuat, cocokuntuk obyekpenelitian,cocok untukkarang lunakdan karangbercabang,memiliki nilaiestetika,bernilaiekonomis
Biaya yangdibutuhkanrelativemahal,rangka besidapatmenyebabkanpencemaran
Sumber ; Anonim 2010. Pelatihan Ekologi Terumbu Karang; Laporan Akhir, Yayasan Lanra Link
Makassar
Pengambilan Data Pertumbuhan Setelah semua koloni karang dipindahkan ke media
transplantasi maka, kegiatan selanjutnya adalah mengukur panjangawal dari koloni yang diambil.
a. Pencatatan data awal (t0) dilakukan setelah semua berkaspatahan karang ditandai dan semua fragmen sudah diletakanpada substrat.
b. Pencatatan pertumbuhan berikutnya (t1) dilakukan padakisaran waktu satu bulan setelah perlakuan dengan mengukurpertambahan tinggi, diameter induk karang dan fragmennya.Data tersebut kemudian dibandingkan dengan data bulansebelumnya. Pengukuran tinggi dilakukan dengan mengukurkoralit aksial cabang tertinggi dari permukaan substrat padakarang sedang pengukuran diameter juga dilakukan denganmengukur cabang terpanjang dan terlebar dari karangtersebut.
c. Jumlah fragmen karang yang masih berada diatas substratdihitung dan diamati kondisi perekatan fragmen karang padasubstrat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangkasorong/caliper dan data yang diperoleh dicatat. Pengukuranpertumbuhan ini dilakukan selama sebulan sekali.
dari samping dari atas dari atas
Gambar Pengukuran panjang dan lebar karang yang ditransplantasikan (sumber; Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,
2007)
DAFTAR PUSTAKA
Abdullohmukhtar, 2011, Tekanan Sedimen Terhadap EkosistemTerumbu Karang Menyebabkan Kematian, blog padawordpress.com.
Ahmad Aditiyawan, 2007, Kajian Ekologi Sumberdaya Karang danPengelolaannya, Makalah, Program Study Pengelolaan SumberdayaPesisir dan Lautan Sekolah Pascasarjana Departemen ManajemenSumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Institut PertanianBogor (IPB) Bogor.
Ahmad Aditiyawan, 2009, Estimasi Daya Dukung Terumbu Karang BerdasarkanBiomasa Ikan Kerapu Macan Di Perairan Sulamadaha, Maluku Utara (SuatuPendekatan Pengelolaan Ekologis), Tesis, Sekolah PascasarjanaInstitut Pertanian Bogor (IPB) Bogor.
Amaryllia. S.; Tuti Yosephine dan Harminto Sundowo, 2003,
Transplantasi Karang Acropora formasa Dana dan Hydnophorarigida Dana: Laju Pertumbuuhan Induk Alam dan Induk HasilTransplantasi serta peresentase keberhasilan hidup fragmen,seminar Riptek Kelautan Nasional, Pusat oenelitianOseanografi LIPI
Anonimous, 2001a. Petunjuk Teknis Transplantasi Karang. DirjenPengembangan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.
--------------, 2001b. Rencana Pengelolaan Ekosistem Wilayah pesisir(Terumbu Karang, Mangrove, Lamun), IPB, Bogor.
--------------, 2010. Pelatihan Ekologi Terumbu Karang; Laporan Akhir,Yayasan Lanra Link Makassar
Bengen, D.G.1995. Sebaran Spasial Karang (Scleratinia) dan Asosiasinya DenganKarakteristik Habitat di Pantai Blebu dan Pulau Sekapal Lampung Selatan.Prosindings Seminar Nasional Pengelolaan Terumbu Karang.LIPI
Coremap dan Yayasan Lara Link Makassar, 2006, Modul TrasplantasiKarang Secara Sederhana, Pelatihan Ekologi Teumbu Karang,Benteng, Selayar 22-24 Agustus 2006.
Dahuri, R. J. Rais, S.P Ginting dan M.J sitepu, 2004. PengelolaanSumberdaya Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Pranya Paramita Jakarta
Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2007, PedomanPenangkaran/Transplantasi Karang Hias Yang Diperdagangkan,http://www.google.blogspot.com
Docklas Roi, 2010, Alat Oseanografi, Fakultas Perikana dan IlmuKelautan Universitas Padjadjaran,http://www.google.blogspot.com
Hari Sutanta. 2006. Kualitas Karang Indonesia Turun Hingga 50%. SatuDunia.
Hutabarat, S dan S.M evans, 1984. Pengantar Oceanografi. UniversitasIndonesia
Kaleka Deslina, 2004 Transplantasi Karang Batu Marga Acropora Pada SubstratBuatan di Perairan Toblolong Kabupaten Kupang, Makalah PeroranganSemester Ganjil 2004 Falsafah Sains (PPS 702) Program S3,[email protected], http://www.google.blogspot.com
Lalamentik, L.T.X.1991.Karang dan Terumbu Karang. Fakultas PerikananUniversitas Sam Ratulangi, Manado
Miftakhul Hakim, 2006, Analisa Usaha Transplantasi Karang Di CV.Dinar Banjar Kesambi Kelurahan Kerobokan Kecamatan KutaUtara Kabupaten Badung Propinsi Bali Laporan Praktek KerjaLapang Sosial Ekonomi Perikanan Universitas BrawijayaFakultas Perikanan Malang
Nontji,A. 2002, Laut Nusantara. Djambata, Jakarta
Nybaken, J.W, 1988 Biologi Laut; Suatu Pendekatan Ekologi, Gramedia.Jakarta
Ofri Johan; Dedi Sudarma dan Suharsono, 2008, tingkat Keberasilantransplantasi Karang Batu di Pulau Pari Kepulauan Seribu,Jakarta, Jurlanal Riset Akuakultur Vol. 3 No 2 tahun 2008Jakarta
Prastowo Mikael, 2011, Snorkeling dan Diving yang RamahLingkungan, Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi)
Romimohtarjo. K dan Juana. 2001 Biologi Laut, Djambatan, Jakarta
Sadrun, 1999, Transplantasi Karang Batu (Stoni Coral) di KepulauanSeribu Teluk Jakarta. Tesis, Program Pascasarjana InstitutPertanian Bogor (IPB) Bogor.
Seminar Riptek Kelautan Nasional, 2003, Keterpaduan program riptekkelautan dalam pembangunan kelautan berkelanjutan. Jakarta, UPTBaruna Jaya
Suharsono,1996. Jenis-jenis Karang yang Umum dijumpai di Perairan Indonesia.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian danPengembangan Oseanologi, Proyek Penelitian dan PengembanganDaerah Pantai, Jakarta
Supriharyono, 2000. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. DjambatanJakarta Tomascik, T. 1991. Coral Reef ecosystem environmentalManagemen Guild. KLH/EMDI. Jakarta
Yusuf rusli, 2005, Laju Pertumbuhan Alami Karang (Acropora formasa) diPerairan Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Perbandingan Dengan PerairanSulamadaha Kota Ternate), Skripsi, Fakultas Perikanan Dan IlmuKelautan Universitas Khairun Ternate
Wikipedia, 2009, Terumbu Karang, Ensiklopedia BebasHttp://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang