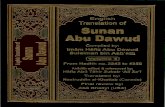DISERTASI - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of DISERTASI - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya
i
RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Studi Islam pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya
Oleh:
Ahmad Agus Ramdlany
NIM. F03417059
PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR PRODI DIRASAH ISLAMIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : AHMAD AGUS RAMDLANY
NIM : F03417059
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/ DIRASAH ISLAMIYAH (STUDI ISLAM)
E-mail address : [email protected] Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (karya Ilmiyah) yang berjudul : beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Surabaya
Penulis
(AHMAD AGUS RAMDLANY )
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: [email protected]
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
vi
vi
ABSTRAK
Judul : Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif
Filsafat Hukum Islam
Penulis : Ahmad Agus Ramdlany
Promotor : Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA.
Prof. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Kata Kunci : Restorative Justice, Filsafat Hukum Islam.
Disertasi ini mengkaji tentang keadilan restoratif yang ada dalam hukum
pidana Islam dilihat dari persepektif filsafat hukum Islam. Pertanyaan yang
diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah sudut pandang filsafat
hukum Islam tentang Restorative Justice dalam hukum pidana Islam? (2)
Bagaimanakah posisi hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum pidana
nasional Indonesia? (3) Bagaimanakah konstruksi pendekatan restorative justice
dalam hukum pidana Islam terhadap pembaruan hukum pidana nasional
Indonesia?
Penelitian ini bersifat Normatif dengan menggunakan statue approach
dan conseptual approach. Bahan pustaka merupakan data dasar yang disebut
sebagai data sekunder. Dengan menggunakan teori dekonstruksi shariahnya an-
Naiem dan teori Za>wajir dari Ibra>hi>m Hosen, penelitian ini menghasilkan temuan,
Pertama; keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah al ‘afwu dan Islah. Perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban atau
keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Korban mendapat
perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan
proses peradilan pidana. Kedua; Hukum pidana Islam sangat menganjurkan
penyelesaian perkara dengan cara perdamaian. Penerapan restorative justice telah
berkembang di masyarakat, baik di desa maupun perkotaaan. Ketiga; Nilai-nilai
keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku.
Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, terutama
korban bukan pada negara.
Restorative Justice dalam hukum pidana Islam dapat berimplikasi pada
efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan akan berkurang, penjara
tidak akan over capacity serta terciptanya keamanan dan ketentraman dalam
masyarakat. Penyerapan nilai-nilai hukum pidana Islam dilakukan melalui proses
objektifikasi istilah-istilah teknis dan bentuk-bentuk hukuman dari hukum pidana
Islam. Dengan metode ini, diharapkan hukum pidana Islam secara subtansial-
kontekstual tetap menjadi bagian dari jiwa pembaruan hukum pidana Indonesia,
meskipun secara formal-tekstual tidak nampak di permukaan, sesuai dengan
kaidah, “Ma laa yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu” (sesuatu yang tidak
mungkin terwujud seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan (yang terpenting
didalamnya) seluruhnya”.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
vii
vii
ABSTRACT
Title : Restorative Justice of Islamic Criminal Law in Islamic Legal
Philosophy
Perspective
Author : Ahmad Agus Ramdlany
Advisor : Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA.
Prof. Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA.
Keywords : Restorative Justice, Islamic law Philosophy
This dissertation examines restorative justice existing in Islamic criminal
law from the perspective of Islamic legal philosophy. The questions raised in this
study are (1) how is the perspective of Islamic law philosophy regarding
restorative justice in Islamic criminal law? (2) how is the position of Islamic
criminal law in the renewal of Indonesian‟s national criminal law? (3) how is the
construction of restorative justice in Islamic criminal law towards the renewal of
Indonesian‟s national criminal law?
This research is normative by using a statue approach and a conceptual
approach. Literature review is basic data which is referred to as secondary data.
By using an-Naiem's shariah deconstruction theory and the Za>wajir theory from
Ibra>hi>m Hosen, this study produces some findings. First; Restorative justice in
Islamic criminal law is known as al 'afwu and Islah. The act of forgiveness and
peace from the victim or his family is seen as something better. The victims
receive refinement from the sanctions imposed, and there is a role of victims in
the criminal justice system and process. Second; Islamic criminal law strongly
encourages settlement of cases in a peaceful manner. The application of
restorative justice has developed in the community, both in villages and cities.
Third; Restorative justice values give equal attention to victims and offenders.
The authority to determine the sense of justice rests with the parties, especially the
victims, not the state.
Restorative Justice in Islamic criminal law can have implications for the
effectiveness of law enforcement in Indonesia. Crime will be reduced, prisons will
be not over capacity and security and peace in society will exist. The absorption of
the values of Islamic criminal law is carried out through a process of objectifying
technical terms and forms of punishment from Islamic criminal law. With this
method, it is hoped that substantially-contextually Islamic criminal law will
remain to be part of the spirit of Indonesian criminal law renewal, although
formally-textually it does not appear on the surface, in accordance with the rule,
"Ma laa yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu" (something that may not be realized
entirely, should not be abandoned (the most important is in it) entirely ".
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
viii
viii
ملخص : العدالت الخصالغت ف القانن الضنائ اإلسالم عالمض
فلسفت الخشرع االسالم. من منظر
: أعمد أغس رمضان بقلم
: األسخاذ الدكخر كاى الغاس أعمد زىرا المشرف
الماصسخر
األسخاذ الدكخر كاى الغاس أعمد إمام مارد :
السالما عدالت الخصالغت، فلسفت الخشرع الكلماث المفخاعت : ال
العدالت الخصالغت ف القانن الضنائ اإلسالم من منظر فلسفت ىذه الدراست حبغذ عن
( 1الخشرع االسالم. حخمزل األسئلت المطرعت ف ىذه الدراست ف رالرت أمر ى: )
كف كان حناقش فلسفت الخشرع االسالم عن العدالت الخصالغت ف القانن الضنائ
غنائ اإلسالم ف حار حضدد القانن الضنائ ( كف كان مقف القانن ال2اإلسالم؟ )
( كف كانج بنت نيش العضالت الخصالغت ف القانن الضنائ 3لضميرت إندنسا؟ )
اإلسالم نغ حضدد القانن الضنائ لضميرت إندنسا؟
اناث ى الب ماد المكخبت .ىذا البغذ المعار باسخخدام نيش الخمارل النيش الخفاىم
االساست الخ حسم بالباناث الزانت. باسخخدام نظرت حفكك الشرعت للنعم نظرت
فقد أشارث نخائش ىذا البغذ إل رالد نقاط ميمت، ى: أال، لقد الزاصر إلبراىم عسن،
اإلسالم بمصطلظ العف ن الضنائ اشخيرث عدالت الخصالغت ف مصطلظ القان
الذ أح من قبل مضن علو أ عائلخو أزك أفعال خبر العف االصالط. فعاالصالط
ىناك در للضغاا ف ،غصل الضغاا عل حغسن من العقباث المفرضتأطبيا.
عذ القانن الضنائ االسالم عل حخمت القضاا رانا، ظام العدالت الضنائت إصراءاحيا.ن
المضخمع ساء أكان مدنيم الت الخصالغت ف سطالعد حطرث. فقد بطرقت الصلظ
. رالزا، فقد أطلقج القم الافرة من العدالت الخصالغت عنات مخسات نغ كال قريمأ
الضانبن الضان المضن علو. فالغق ف حعن العدالت مفض إل أد الضانبن، لسج
.حقع عل الدلت
عالت حنفذ الغكم ف إندنسا، ن الضنائ االسالم حؤرر إل فالعدالت الخصالغت ف القان
قبضت ، ف طاقخيا صبظ المضخمع ف االمن السالمسخنقص الضرمت لن حفرط السضن
قم الغكم الضنائ االسالم حعمل عن طرق مضعت المصطلغاث الخقن ىئاث العقبت
لغكم الضنائ االسالم قت، رص أن كن امن الغكم الضنائ االسالم. بيذه الطر
نصا -غم أن شكلانائ ف إندنسا، رمن حضدد الغكم الضصر اما مق-مضعا
رك كلو" ما ال درك كلو ال خالظير، مطابق مع القاعدة "
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
xi
xi
DAFTAR ISI
Halaman Sampul........................................................................................ i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah............................................. ii
Halaman Persetujuan Pembimbing............................................................ iii
Pedoman Transliterasi…………………………………………………….. iv
Motto.......................................................................................................... v
Abstrak Indonesia………………………………………………..……...... vi
Abstrak Inggris….………………………………………………..……...... vii
Abstrak Arab……..………………………………………………..…….... viii
Kata Pengantar…………………………………………………..….......... x
Daftar Isi………………………………………………………………...... xii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………. 1
A. Latar Belakang………………………………………………………. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah………………………………….... 8
1. Identifikasi masalah ...................................................................... 8
2. Batasan masalah .............................................................................. 9
3. Rumusan Masalah ........................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….. 10
D. Kegunaan Penelitian.……………………………………………….... 10
E. Kerangka Konseptual…………………………………....…………… 11
F. Studi Terdahulu…………………………………....…………………. 29
G. Pendekatan dan Metode Penelitian ………………………………….. 32
H. Sistematika Pembahasan…………………………………....……….. 41
BAB II KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
ISLAM…………………………………....……………………. 43
A. Filsafat Hukum Islam……………..………………………………….. 43
1. Pengertian Filsafat Hukum Islam……………………………… 43
2. Prinsip-Prinsip Dasar Filsafat Hukum Islam………………….. 58
3. Konsep Filsafat Hukum Islam…………………………………. 63
B. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam ……………………………. 69
1. Pengertian Keadilan…………………………………………… 69
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
xii
xii
2. Konsep Keadilan Dalam Islam………………………………… 74
3. Bentuk-Bentuk Keadilan Dalam Islam………………………… 80
4. Keadilan Dalam Pandangan Filosof Islam…………………….. 91
C. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Umum……………………………. 104
1. Konsep Keadilan…………..……………………….…………... 104
2. Bentuk-Bentuk Keadilan …………………………….………... 112
3. Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM)….…….…………… 119
BAB III RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA
ISLAM …………………………………………….……...……. 126
A. Restorative Justice ……………………………………………..……… 126
1. Pengertian Restorative Justice…………………………………. 127
2. Konsep Restorative Justice…………………………………….. 135
3. Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia……………………. 142
B. Hukum Pidana Islam……………………………………………..…..… 148
1. Pengertian Hukum Pidana Islam…………………..………..... 148
2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Islam……………………… 157
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam…… 166
C. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Nasional Indonesia……………………………………………………. 179
1. Fleksibilitas Hukum Pidana Islam…………………………….. 179
2. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia…………. 194
BAB IV PRESPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG
RESTORATIVE JUSTICE …………………………………….. 211
A. Sudut Pandang Filsafat Hukum Islam Tentang Restorative Justice
dalam Hukum Pidana Islam …………..…………………………….…. 211
1. Keadilan Restorative Dalam Hukum Pidana Islam …………… 212
2. Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana …………………………………………………………. 218
3. Konsep Al-„Afwu (Pemaafan) Dalam Hukum Pidana Islam…... 230
4. Pembaharuan Hukum Pidana Islam Dalam Pembangunan
Hukum Pidana Nasional……………………………………….. 238
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
xiii
xiii
B. Konstruksi Pendekatan Restorative Justice Hukum Pidana Islam
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional………………….…….. 245
1. Ijtihad Umar Bin Khattab……………………………………… 246
2. Beberapa Pendekatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Nasional……………………………………………………….. 252
3. Prospek Pendekatan Restorative Hukum Pidana Islam
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana nasional………………… 271
C. Restorative Justice Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana
Nasional……………………………………………………………….. 277
1. Transformasi Restorative Justice Hukum Pidana Islam Bagi
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional……………………….. 278
2. Restorative Justice dan Peradilan di Indonesia……………….. 282
3. Praktik Restorative Justice Arab Saudi dan Prancis .................. 292
BAB V PENUTUP…………..………….………………………………. 304
A. Kesimpulan…………….………………………………….………….. 304
B. Implikasi Teoritik……..………………………….…………………… 305
C. Keterbatasan Penelitian……………………………………………….. 306
D. Rekomendasi………………………………………………………….. 307
DAFTAR KEPUSTAKAAN….…………………………………………. 309
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno
pada 17 agustus 1945,1 maka sejak saat itu, bangsa Indonesia mempunyai
keinginan untuk memiliki produk hukum sendiri, mengganti hukum peninggalan
Belanda. Berbagai kegiatan ilmiah yang berskala lokal maupun nasional guna
merumuskan pembentukan hukum nasional telah dilakukan, baik oleh pemerintah
maupun oleh lembaga pendidikan tinggi. Para pakar hukum pun banyak yang
telah mengusulkan tentang profil hukum pidana nasional ke depan.
Pemerintah Indonesia juga telah berupaya membuat hukum pidana
nasional produk sendiri dengan menyusun Rancangan Undang-undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) yang hingga sekarang belum final dan terus dilakukan
perbaikan. Pembangunan sistem hukum tidak bisa lepas dari politik hukum. Arah
politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya
menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Rencana
pembangunan materi hukum termuat di dalam Program Legislasi Nasional yang
disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah.2
1 Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari jum‟at, 17 agustus 1945 tahun
masehi, atau tanggal 17 agustus 2605 menurut tahun jepang, yang dibacakan oleh Soekarno
dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di jalan pegangsaan timur 56 Jakarta
pusat. Http://id.m.wikipedia.org./2019/02/Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2 Program legislasi nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan
Undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan Prolegnas di
lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR,
DPD, dan/atau masyarakat. Hal ini Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. https//id.m.wikipedia.org. 2019/02/Program
Legislasi Nasional 2015-2019.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
2
Hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam penting untuk
diperhitungkan sebagai sumber pembangunan hukum pidana nasional. Secara
faktual hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (the living law)3 dalam
masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Hukum pidana Islam
dapat diserap sebagai sumber materiil dalam pembangunan hukum pidana
nasional meskipun tidak semuanya. Untuk ketentuan tindak pidana pembunuhan
dan pelukaan atau penganiayaan dapat diserap delik maupun sanksinya. Sanksi
ganti kerugian (diyat) yang di dalamnya ada proses perdamaian lebih sesuai
dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, terlebih jika dilihat dalam konten
masyarakat Indonesia yang dikenal pemaaf, mengedepankan kekeluargaan dan
musyarawarah dalam menyelesaikan sengketa. Banyak kasus hukum, khususnya
yang dalam KUHP disebut sebagai kelalaian sehingga menyebabkan nyawa orang
lain hilang, yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti
kerugian. Penyelesaian tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan
cara perdamaian adalah mirip dengan ketentuan qis{a>s{-diyat dalam hukum pidana
Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Islam telah membentuk
kesadaran hukum masyarakat.
Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya berorientasi
pada pelaku, sehingga jika diterapkan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang
lain, tidak memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya. Seiring
berkembangnya wacana global tentang perlunya pendekatan restorative justice,
3 Martin Kryger menyatakan bahwa “law as a tradition” bahwa hukum adalah produk budaya (law
as a product of culture). Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan
hukum atau sebaliknya, hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan
perkembangan budaya masyarakatnya. Hal itu menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan
dari perkembangan masyarakat. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa
masyarakat merupakan fabric of rules, bahwa masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan
hukumnya sesuai dengan tipe, jenis dan budaya masing-masing.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
3
maka pendekatan tersebut perlu diatur dalam RUU KUHP. Pendekatan restorative
justice memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban atau keluarganya.
Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengganti
kerugian, korban atau keluarganya memaafkan serta menerima ganti kerugian, dan
hubungan ke depan dapat dipulihkan. Hal ini juga ada kemiripan dengan
ketentuan qis{as{-diyat dalam hukum pidana Islam. Pidana qis{a>s{ (setimpal) dan
diyat (ganti rugi) menjadi hak korban atau ahli warisnya, sehingga dapat
memberikan amnesti (pemaafan) kepada pelaku. Apabila memaafkan, gugurlah
pidana qis{a>s{ diganti dengan diyat (ganti rugi), bahkan tanpa diyat sama sekali.
Ketentuan qis{a>s{-diyat berorientasi pada perhatian dan perlindungan pada korban,
dan penyelesaiannya melalui perdamaian atau pemaafan (is{la>h{/al afwu {).
Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak
korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang
harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap
korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.4 Hal ini dapat dilihat
dalarn KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban,
pernbahasannyapun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana,
rnelainkan hanya sebagai warga negara biasa yang rnernpunyai hak yang sarna
dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam istilah yang digunakan
dalam menunjuk seorang korban.5
Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling
menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan
4 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Pres, 2005), 2. 5 Ada beberapa Istilah lain yang menunjuk terhadap korban, antara lain terdapat dalam Pasal
80-81 KUHAP: pihak yang berkepentingan, Pasal 98-99: pihak yang dirugikan dan Pasal 108:
Pengadu atau pelapor.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
4
sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.
Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh
pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.
Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya
berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.6
Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya
diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan,
dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.
Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi
di persidangan, ia dikenakan sanksi. Perlindungan hukurn terhadap korban selama
ini baru mencapai taraf keadilan prosedural,7 belum mencapai cita-cita dan
keinginan dari tujuan hukum yang sebenarnya yakni keadilan substansial.8
Padahal eksistensi korban dalam suatu pelanggaran terhadap hukum pidana
menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi
terhadap harus diakuinya kepentingan korban. Untuk itu diperlukan
pemberdayaan posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya
perlindungan hukum secara substansial.
6 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guhom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norma dan Realita, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 24. 7 Keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang saja, Thomas Aquino menyatakan bahwa
keadilan prosedural adalah keadilan yang berhubungan dengan proses dan kelayakan prosedur-
prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan kepentingan-kepentingan organisasi. 2019/02.
www.suaramerdeka.com. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu
dan mempunyai sasaran utama peraturan, hukum, ataupun undang-undang. Prosedur ini tidak
bisa lepas dari upaya legitimasi tindakan, Keadilan yang lahir hanya karena melaksanakan
kaedah formil dan materil peraturan perundang-undangan, 2019/02. www.kompas.com. 8 Keadilan yang berhubungan dengan objek legislasi hukum positif yang terkandung di dalam
setiap bentuk hukum yang berlaku. Dengan keadilan substansif setiap bentuk hukum yang
berlaku pada dasarnya merupakan manifestasi ikatan yurisdiksi dan mendistribusikan beban atas
dasar kesamaan yang proporsional. 2019/02. http://books.google.co.id, Keadilan yang lebih
mendekatkan diri dan mendengar jeritan korban.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
5
Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya
untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya
suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang
memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law).
Kedudukan korban yang tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana
dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang menganut keadilan
retributif (retributive justice), penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan
untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan
aspek kerugian yang diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk
pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh
korban.
Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam seperti qis{a>s{-diyat secara
filosofis lebih menjanjikan dapat memberikan manfaat dan kepastian keadilan
sebagaimana tujuan utama dalam hukum pidana. Menurut hukum yang berlaku di
Indonesia, yang berhak melaksanakan proses pemidanaan adalah penguasa,
korban tidak dilibatkan. Akibat korban tidak dilibatkan, dalam pelaksanaan pidana
banyak menimbulkan masalah bagi korban, misalnya korban merasa tidak
mendapat perlindungan dari Negara dan tidak puas karena kerugian yang diderita
korban tidak tergantikan. Untuk tindak pidana menghilangkan nyawa orang
lain/penganiayaan, proses hukum tanpa melibatkan korban atau keluarganya tentu
tidak akan memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya.
Keadilan yang dituju hanyalah keadilan yang diciptakan dan menurut
ukuran penguasa, yang tentu saja tidak sama dengan keadilan menurut korban.
Model pemidanaan demikian perlu untuk dikaji kembali. Sebab untuk tindak
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
6
pidana terhadap nyawa, keadilan tidak dapat terwujud tanpa memperhatikan
korban atau keluarganya, dan harmoni dalam masyarakat tidak dapat
dikembalikan. Penyelesaian perkara pidana yang lebih adil adalah dengan cara
melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Model seperti
ini di Indonesia telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat, yaitu
musyawarah mufakat, yang dalam hukum pidana Islam berlaku untuk tindak
pidana qis{a>s{-diyat melalui perdamaian atau pemaafan (is{la>h{/al afwu{) dan mirip
dengan pendekatan restorative justice yang saat ini menjadi wacana global untuk
diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana.
Dalam kenyataanya di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan
pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terharap
ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian konflik
dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia
seperti dinyatakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Wukir Prayitno bahwa
budaya hukum di Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai
karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan
perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyakarat,
mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha terpuji sehingga dalam
menyelesaikan konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi, terutama
dalam masyarakat Jawa dan Bali.9
Restorative justice atau is{la>h{ memiliki landasan filosofis dan teologis yang
mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat,
mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat
9 Wukir Prayitno, Modernisme Hukum Berwawasan Indonesia, (CV. Agung, Semarang, 1991), 21.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
7
dengan pemaafan, menghentikan tuntut menuntut dan salah menyalahkan.
Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan,
melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.10
Restorative justice
atau is{la>h{ adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku
untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan
yang terjadi. Dalam hal ini, Is{la>h{ { merupakan pilihan yang menjadi hak preogratif
dari korban maupun ahli warisnya.11
Penyelesaian perkara tindak pidana melalui Restorative justice atau Is{la>h{
juga tertera dalam hukum Islam, hal ini dapat kita lihat dari beberapa nas{ yang
dijadikan landasan is{la>h{ {, antara lain surat Al-Hujurat ayat 10:
صإ أ ف وة خ إ ون ن ؤم م ل اا نم م ك وي خ أ ي واب ح رحون ل ت م لمك ع ل وااللمه ت مق وا
Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”
Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 224:
ي ب وا ح ل ص وت وا ق ت م وت روا ب ت ن أ م ك ن ا لي ة رض ع اللمه وا ل تع ول لنماس ايم ل ع يع س واللمه
Artinya : “Jangahlah kamu jadikan (nama) Alla>h dalam sumpahmu
sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan is{lah{ di
antara manusia. dan Alla>h Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Proses Restorative justice atau is{la>h{ terjadi karena adanya perspektif yang
berubah dari korban dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Perubahan
perspektif ini menyebabkan cara penyelesaian yang ditempuh pun berubah
10 A. Yani Wahid, Is{lah{, resolusi konflik untuk rekonsiliasi, Kompas, 16 Maret 2001. 11 Tim Penyusun Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berjudul
Monitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok., Artikel ini didapat memalui akses
internet pada tanggal 22 Maret 2019.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
8
tergantung kondisi dan keinginan korban. Penyelesaian Tindak pidana melalui
Restorative justice atau is{la>h{ memang merupakan jalan keluar yang sangat baik,
namun pada kenyataanya, penyelesaian secara Restorative justice atau is{la>h{ tak
selalu bisa menghentikan penyelidikan perkara dalam hukum positif oleh sebab
yang diatur oleh hukum. Namun, berbeda halnya dalam hukum pidana Islam,
Restorative justice atau Is{la>h{ merupakan jalan yang sangat baik dan bisa
dilakukan sebelum adanya keputusan dari hakim. Maka untuk menjawab
problematika tersebut, penulis tertarik untuk menulis disertasi dengan judul
Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum
Islam.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan
pokok yang dapat diidentifikasi, diantaranya yaitu:
a. Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (the living law) dalam
masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Kaitannya
dengan pembaharuan hukum pidana nasional, hukum pidana Islam
sebagai bagian dari hukum Islam, penting untuk diperhitungkan sebagai
sumber pembaharuan hukum pidana nasional.
b. Hukum pidana Islam dapat diserap sebagai sumber materiil dalam
pembangunan hukum pidana nasional meskipun tidak semuanya. Untuk
ketentuan tindak pidana pembunuhan dan pelukaan atau penganiayaan
dapat diserap delik maupun sanksinya.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
9
c. Sanksi ganti kerugian (diyat ) yang di dalamnya ada proses perdamaian
(s}ulh{), lebih sesuai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Apalagi
masyarakat Indonesia dikenal pemaaf, mengedepankan kekeluargaan dan
musyarawarah dalam menyelesaikan sengketa.
2. Batasan Masalah
Penelitian ini memfokuskan pada urgensi dan eksistensi dua pokok
masalah, yaitu:
a. Perspektif filsafat hukum Islam terhadap restorative justice dalam hukum
pidana Islam sebagai bahan hukum dalam upaya pembaruan hukum pidana
di Indonesia;
b. Relasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional, dalam hal ini
hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam yang sudah berlaku
dan dilaksanakan, dalam kehidupan masyarakat Indonesia;
c. Menyuguhkan kontribusi dan strategi nilai-nilai Restorative Justice dalam
hukum pidana Islam terhadap jiwa dan nafas pembaharuan hukum pidana
Nasional.
3. Rumusan Masalah
Dari seluruh penjelasan pada latar belakang, identifikasi masalah dan
batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sudut pandang filsafat hukum Islam tentang Restorative
Justice dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah posisi hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum
pidana nasional Indonesia?
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
10
3. Bagaimanakan konstruksi pendekatan restorative justice dalam hukum
pidana Islam terhadap pembaruan hukum pidana nasional Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menemukan relasi filsafat hukum Islam dengan Restorative justice
dalam hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam yang hidup
dan dilaksanakan di Indonesia.
2. Untuk menemukan bentuk-bentuk relasi hukum pidana Islam dengan
hukum pidana nasional Indonesia.
3. Untuk menemukan kontribusi yang diberikan oleh hukum pidana Islam
terhadap pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, sehingga
hukum pidana Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, nilai-
nilainya dapat diterima dan dilaksanakan dalam hukum pidana nasional
Indonesia.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu; kegunaan
teoritis dan kegunaan praksis. Adapun penjelasannya di bawah ini:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan
pemikiran dan wawasan teoritis mengenai kajian urgensi Restorative Justice
dalam Hukum Pidana Islam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana
Nasional kita.
2. Kegunaan Praksis
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
11
Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan
wawasan bagi berbagai pihak, diantaranya:
a. Bagi Praktisi Akademisi; penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumbangan wawasan keilmuan tentang kajian urgensi Restorative
Justice dalam Hukum Pidana Islam;
b. Bagi Praktisi Penyusun Pembaharauan Hukum Pidana Indonesia;
penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan keilmuan mengenai
alat untuk mengukur dan berkontribusi dalam efektifitas penggunaan
Restorative Justice dalam pidana Islam;
c. Bagi praktisi sosial ataupun masyarakat, hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai sumbangan wawasan dalam rangka pemahaman
dan pemetaan hubungan nilai-nilai hukum pidana Islam dengan
penegakan hukum yang efektif dan efisien di masyarakat.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah sebuah bentuk kerangka berfikir yang dapat
dipakai sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah. Umumnya kerangka
konseptual ini menggunakan pendekatan ilmiah agar memperoleh hasil yang tepat
dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang perlu
mendapatkan penjelasan lebih detail diantaranya sebagai berikut:
1. Restorative Justice.
Restorative justice menurut pandangan para filolosofis dan ahli hukum
adalah as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention (sebagai
filsafat, proses, gagasan, teori, dan intervensi). Restorative justice adalah
peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
12
dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif
yang melibatkan semua pihak (stakeholders).12
Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the
harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished
through cooperative processes that include all stakeholders.13
(Restorative
justice adalah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan
akan kerusakan yang disebabkan atau ditunjukkan oleh perilaku jahat. Ini
adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, melalui proses kerja
sama yang melibatkan semua pihak).
Definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:
Restorative justice is a valued based approach to responding to
wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the
person causing the harm, and the affected community.14
(Keadilan
restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menyelesaikan masalah
dan konflik, dengan fokus keseimbangan antara orang yang dirugikan,
orang yang menyebabkan kerusakan, dan masyarakat yang terkena
dampak).
Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan criminal
dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/
masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali
pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari restorative justice
adalah empowerment bahkan empowerment ini adalah jantungnya restoratif (the
heart of the restorative ideology), oleh karena itu restorative justice
keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.15
12 Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braith-waite, Umbreit and Cary, Richardson,
Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, Social Welfare and
Restorative Justice, Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1
Pagesrecord No. 55-68, 2009, (London Metropolitan University Department of Applied Social
Sciences), 56. 13
lihat dalam http://152.118.58.226 - Powered by Mambo Open Source Generated; 2019/02/21. 14 lihat dalam http://152.118.58.226 - Powered by Mambo Open Source Generated; 2019/02/2. 15 C. Barton, Empowerment and Retribution ini Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds),
Restorative Justice: Philosophy to Practice. Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/
Dartmouth, 55-76.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
13
Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima
dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide restorative
justice hendak mengatur kembali peran korban, dari semula yang pasif menunggu
dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan, diarahkan
untuk berubah dengan cara diberdayakan, sehingga korban mempunyai hak
pribadi untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pidana. Dalam literatur
tentang restorative justice, dikatakan bahwa “empowerment” berkaitan dengan
pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).16
Para sarjana
memaknainya sebagai berikut:
“…..has described empowerment as the action of meeting, discussing and
resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional
needs. To him, empowerment is the power for people to choose between
the different alternatives that are available to resolve one‟s own matter.
The option to make such decisions should be present during the whole
process”.17
(.......pemberdayaan digambarkan sebagai tindakan bertemu,
mendiskusikan dan menyelesaikan masalah peradilan pidana untuk
memenuhi kebutuhan materiil dan emosional. Pemberdayaan adalah
kekuatan bagi orang untuk memilih di antara berbagai alternatif yang
tersedia untuk menyelesaikan masalah sendiri. Pilihan untuk membuat
keputusan seperti itu, harus ada dalam seluruh proses”).
Kongkritnya, empowerment atau pemberdayaan dalam konteks restorative
justice adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau
masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian
masalah pidana (resolution of the criminal matter). Hal ini merupakan alternatif
atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan.
Respon terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar
peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti
dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa
16 Ketiga pihak tersebut oleh Mc Cold dikatakan sebagai stakeholder perkara pidana. 17 Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, Restorative Justice and the Active
Victim: Exploring the Concept of Empowerment, Journal TEMIDA, Mart 2011, 8-9.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
14
kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. Restorative
justice justru sebaliknya mengusung falsafah intergrasi yang solutif, masing-
masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu
konsep restorative justice bisa dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah
dalam penyelesaian perkara pidana.
Konsep teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting
dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem
peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban
(criminal justice system that disempowers individual); kedua, menghilangkan
konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the
conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami
sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order
to achieve reparation).18
Praktik dan program restorative justice tercermin pada tujuannya yang
menyikapi tindak pidana dengan: pertama, identifying and taking steps to repair
harm (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki
kerugian/kerusakan); kedua, involving all stakeholders (melibatkan semua pihak
yang berkepentingan) dan; ketiga, transforming the traditional relationship
between communities and their governments in responding to crime.
Transforming the traditional relationship yaitu transformasi dari pola dimana
masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana
18 Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, Restorative Justice and the Active
Victim: Exploring the Concept of Empowerment, Journal TEMIDA, Mart 2011; 8-9.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
15
menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/
korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.19
Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadap-
hadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau
integrasi, persoalannnya adalah kejahatan yang dilakukan sebagai tindak pidana
oleh pelaku adalah kejahatan terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap
negara, sehingga akan sangat baik sekali kalau penyelesaiannya adalah dilakukan
oleh pihak-pihak yang berperkara, tidak semata-mata diserahkan atau diselesaikan
oleh negara begitu saja.
Restorative Justice is commonly known as a theory of criminal justice that
fo-cuses on crime as an act by an offender against another individual or
community rather than the state.20
(Keadilan Restoratif umumnya dikenal
sebagai teori peradilan pidana yang berfokus pada kejahatan sebagai
tindakan oleh pelaku terhadap individu atau komunitas lain dari negara).
Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya
memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya
pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat
dan memelihara perdamaian yang adil. Dengan kata lain ketiga prinsip tersebut
mengandung unsur-unsur sebagai berikut; Pertama, justice requires that we work
to restore those who ha-ve been injured (keadilan menuntut kita bekerja untuk
memulihkan mereka yang terluka); kedua, those most directly involved an affected
19 McCold and Wachtel, Restorative practices, The International Institute for Restorative
Practices (IIRP), New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal,
Vol. 85-101, 2003, 7. 20 Lihat pula pendapat Jarem Sawatsky sebagai berikut: The criminal justice system never asks
what the victim needs, what the offender needs or what the immediate community needs. It
focuses on what the state needs at the exclusion of other‟s „needs. It is interested in assessing
guilt and handing out punishment.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
16
by crime should have the opportunity to participate fully in the response if they
wish (mereka yang terlibat dan terkena dampak kejahatan harus memiliki
kesempatan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam respons jika mereka mau);
dan ketiga, government‟s role is to preserve a just public order, and the
community is to build and maintain a just peace (peran pemerintah adalah untuk
memelihara ketertiban umum, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan
masyarakat).21
Justice Peace dalam restorative justice ditempuh dengan restorative
conferencing yaitu mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk
mencari atau memutuskan cara yang terbaik mengatasi dampak atau akibat dari
kejahatan (decide how best to repair the harm). Selain itu pertemuan (confe-
rencing) juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada korban untuk
menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan
menyampaikan keinginannya; pelaku dapat mendengar langsung bagaimana
perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang
lain pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau
kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti
rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.22
Memahami restorative justice pastinya akan menemukan semangat lebih
pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial daripada
mengedepankan penerapan aturan/hukum yang menghadapkan pelaku dengan
aparat pemerintah. Adapun semangat yang terkandung di dalamnya meliputi:
21 Lihat Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wiki-pedia.org/wiki/Restorative justice;
2019/02/21. 22 Bandingkan dengan O Connell, 1998 & Morris and Max-well, 2001, Restorative or Community
Conferencing, The IIRP, 17
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
17
search solutions (mencari solusi); repair (memperbaiki); reconciliation
(perdamaian); dan the rebuilding of relationships (membangun kembali
hubungan). Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan
sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan
yang progresif.23
2. Hukum Pidana Islam
Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jina>yat atau
jari>mah. Jina>ya>t dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak
pidana. Jina>yah merupakan bentuk verbal noun dari kata jana>. Secara etimologi
jana> berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jina>yah diartikan perbuatan dosa
atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jina>ya>t mempunyai beberapa
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh „Abd al-Qa>dir ‘Awdah bahwa jina>ya>t
adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta
benda, atau lainnya.24
Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jina>ya>h mengacu
kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada
perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqah{a’, perkataan jina>ya>t berarti perbuatan
perbuatan yang dilarang oleh syara‟. Meskipun demikian, pada umunya fuqah{a’
menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang
menurut syara. Meskipun demikian, pada umumnya fuqah{a‟ menggunakan istilah
tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa,
23 Marc Levin, Restorative justice in Texas: Past, Present and Future, (Texas: Texas Public Policy
Foundation, 2005), 5-7. www.TexasPolicy.com 2019/02/21. 24 Abd al-Qa>dir Audah, al-Tasyri> al-Jina>’i> al-Isla>mi>;Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wadh’i>, Jilid I,
Beiru>t: Muasasah al-Risa>lah Litiba’>ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>, 1992, 79-99.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
18
seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqah{a’ yang
membatasi istilah jina>ya>t kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan
hukuman hudu>d dan qis{a>s{, tidak temasuk perbuatan yang diancam dengan ta’zi >r.
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jina>ya>t adalah jari>mah{, yaitu larangan-
larangan syara‟ yang diancam Allah dengan hukuman h{ad atau ta’zi >r.25 Secara
umum, pengertian jina>ya>t sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu
hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota
badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. jari>mah{ (kejahatan)
dalam Hukum Pidana Islam (jina>ya>t) meliputi, jari>mah{ hu>dud, qis{{a>s}, diyat dan
ta’zi >r.26
Macam macam tindak pidana (jari>mah) dalam Islam dilihat dari berat
ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu hudu>d, qis{as{ diyat dan ta’zi >r.27
a. Ja>rimah >’ H}udu>d.
Jari>mah >’ hudu>d yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman
hukumannya ditentukan oleh nas{ yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had
yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa
dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang
mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam
ja>rimah hudu>d ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (qadzf), mencuri (sirq),
perampok dan penyamun (hira>bah), minum-minuman keras (syurbah), dan murtad
(riddah).
25 Ahmad Jazuli, Fiqh jinayah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan I, 1999), 21. 26 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35. 27 Abd al-Qa>dir Audah, al-Tasyri>’ al-Jina>’i ‘al-Isla>mi>; Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wad{’i>, Jilid I,
Beirut: Muasasah al-Risa>lah Litiba>’ah wa al-Nas{ir wa al-Tauzi>, 1992, 79-99.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
19
Jari>mah hudu>d bisa berpindah menjadi ja>rimah ta’zi >r bila ada syubha>t,
baik itu shubhat fi>> al-fi‘li, fi>> al-fa>‘il, maupun fi> al-mah{al. Demikian juga bila
jari>mah hudu>d tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan
pembunuhan. Bentuk lain dari jari>mah ta’zi >r adalah kejahatan yang bentuknya
ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip-prinsip dan tujuan
syari‟ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi
sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain lain. Kejahatan
hudu>d adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam.
Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak
mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan
dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman had. Sementara qis{as{
berada pada posisi diantara hudu>d dan ta’zi >r dalam hal beratnya hukuman. Ta’zi >r
sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.
b. Jari>mah Qis{a>s{-Diyat .
Jari>mah qis{a>s{-diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qis{as{
dan diyat . Baik qis{as{ maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan
batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan
(si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak
Allah semata. Penerapan hukuman qis{as{-diyat ada beberapa kemungkinan,
seperti hukuman qis{as{ bisa berubah menjadi hukuman, hukuman diyat apabila
dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qis{as{
diyat antara lain pembunuhan sengaja (qotl amd), pembunuhan semi sengaja
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
20
(qotl sibh amd), pembunuhan keliru (qotl khat {a>‘), penganiayaan sengaja
(jarh‘amd) dan penganiayaan salah (jarh khat {a‘).28
Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan
sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia
hanya diberi hukuman untuk membayar diyat yaitu denda senilai 100 onta. Di
dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti („uqu>bah
badaliah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (‘uqu>bah as{liyah)
dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Keberadaan uqubah
dalam Islam, yang berfungsi sebagai pencegah, telah disebutkan dalam al-Qur‟an:
ون ق ت م ت م لمك ع ل اب ب الل ول اأ ي اة ي ح اص ص ق ال ف م ك ول
Artinya : “Dan dalam qis{as{ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” (al-Baqarah:
179).
c. Jari>mah Ta’zi >r.
Secara bahasa ta‘zi>r merupakan mas{dar (kata dasar) dari „azzaro yang
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan,
membantu. Ta‘zi>r juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut
dengan ta‘zi>r, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum
untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.
Sementara para fuqaha mengartikan ta‘zi>r dengan hukuman yang tidak ditentukan
oleh al Qur‟an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak
Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum
28
Abd al-Qa>dir ‘Audah, al-Tasyri> al-Jina>’i al-Isla>mi>; Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wad{’i>, Jilid I,
Beirut: Muasasah al-Risa>lah Litiba>’ah wa al-Nas{ir wa al-Tauzi>’,1992, 87.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
21
dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta‘zi>r sering juga
disamakan oleh fuqaha> dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak
diancam dengan hukuman had atau kaffa>ra>t.29
Ta‘zi>r adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur‟an dan hadits
yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Alla>h dan hak hamba yang
berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk
tidak mengulangi kejahatan serupa. Penentuan jenis pidana ta‘zi>r ini diserahkan
sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Alla>h SWT
telah menetapkan hukum-hukum uqu>bah (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam
peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus. Sebagai pencegah, karena ia
berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal; dan sebagai penebus, karena
ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat.30
Demikian pula halnya dengan hukuman-hukuman lainnya, sebagai bentuk
pencegahan terjadinya kriminalitas yang merajalela.31
Bisa dikatakan pula, bahwa ta‘zi>r adalah suatu jari>mah yang diancam
dengan hukuman ta‘zi>r (selain had dan qis{as{-diyat ). Pelaksanaan hukuman
ta‘zi>r, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan
itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan
sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jari>mah ta‘zi>r tidak ditentukan
ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi
diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari‟ah
29 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45. 30 Ahmad Jazuli, Fiqh jinayah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan I, 1999), 21. 31
Musthafa Abdullah, dkk. Intisari Hukum Pidana, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983), 123.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
22
mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada
pelaku jari>mah.
Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi
terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi
pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup,
lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan
jarimah ta‘zi>r prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga
kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan
(bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta‘zi>r harus sesuai dengan prinsip
syar‘i (nas{).32
3. Maqa>s}id Shari>’ah
Sesuai dengan latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah,
maka penelitian ini mempertimbangkan beberapa teori dengan mengambil
pendekatan maqa>s}id (fisafat hukum Islam). Maqa>s}id Shari>’ah merupakan kajian
yang mempunyai posisi sentral dalam ijtihad kaum muslimin pada setiap masa,
termasuk di masa mendatang. Maqa>s}id Shari>’ah merupakan kajian ijtiha>diyah
yaitu menampakkan hukum yang tidak ada nas{ (dalil) dalam Al-Qur‟an maupun
hadits. Setiap mujtahid dari berbagai bidang keilmuan wajib hukumnya untuk
mengetahuinya karena Maqa>s}id Shari>’ah bertujuan untuk mencari tahu dasar
landasan atau sebab mengapa hukum itu diturunkan. Seorang muslim yang
menegakkan maqa>s{id, berarti telah menciptakan keselamatan dan kesejahteraan
pada ruang-ruang privat maupun publik yang disebut maslahat. Maslahat berarti
bermanfaat bagi banyak orang. Dengan kata lain, menjaga maslahat berarti
32
Ahmad Jazuli, Fiqh jinayah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan I, 1999), 21.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
23
melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum dari tindakan seseorang
atau sekelompok orang yang hendak membawa kerusakan.
Konsep maqa>s{id sendiri dikembangkan sejak abad ke-12 oleh Abdul
Ha>mid Al-Ghaza>li>33
(wafat 1.111 M) melalui penjagaan atau perlindungan lima
aspek fundamental seorang manusia, yakni: a. Melindungi agama, b. Melindungi
akal, c. Melindungi badan/jiwa, d. Melindungi keturunan dan e. Melindungi harta.
Kemudian, konsep Maqa>s{id mengalami revisi dan pengembangan lebih lanjut
pada abad ke-14 oleh Ibnu Taimiyah (wafat 1.328 M) dan kemudian
dikembangkan lagi oleh muridnya, yaitu Al-Sya>tibi> (wafat 1.388 M) menjadi
landasan filosofi hukum Islam yang baru34
. Al-Sya>tibi dalam kitab al-Muwa>faqat
fi> us{u>li al-syari>‘ah menjelaskan bahwa Maqa>s}id Shari>’ah dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu d{aru>riyya>t (hak primer), ha>jiyya>t (hak sekunder) dan tah{si>niyya>t
(hak suplementer).35
Pertama, D{aru>riyya>t; terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan
esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. D{aru>riyya>t adalah adalah
segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan.36
Adapun lima aspek perlindungan fundamental kehidupan manusia yang
dikembangkan Al-Ghazali tersebut di atas termasuk dalam kategori ini. Kedua,
Ha>jiyya>t; yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan hak yang
dimaksud, tapi tidak mencapai darurat. Dalam arti bila pemenuhannya tidak bisa
33 Al-Ghazali, al-Mustasfa min „Ilm al-Ushul, Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 287. 34
Halim Rane. The Relevance of a Maqasid Approach For Political Islam Post Arab Revolutions,
(Journal of Law and Religion, Vol. XXVIII, 2013), 493-494. 35 Abu> Isha>k As-Sya>tibi>. al-Muwa>faqa>t fi Us}u>li al-Syar>i’ah, Beiru>t: (Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah.
2004), 221. 36
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
24
terpenuhi, maka hak dasarnya masih bisa terlindungi, meski sangat lemah.37
Contoh yang termasuk dalam perlindungan kategori ini adalah seperti menjaga
hubungan kekerabatan, menghormat hak tetangga, kewajiban memenuhi
perjanjian yang telah disepakati dan mencegah kerusakan lingkungan.38
Ketiga,
tah{si>niyya>t; dapat dimaknai sebagai hal-hal yang tidak mendesak dan sangat tidak
penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi, tah{s>iniyya>t akan
menyempurnakan pelaksanaan hak-hak yang lain.39
Contoh yang termasuk dalam
perlindungan kategori ini adalah persamaan hak politik dan kesetaraan gender.
Pembaharuan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan
perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut
pengertian ini pembaharuan (reform)40
semakna dengan pembangunan.
Sedangkan hukum pidana nasional merupakan bagian sistem hukum nasional
yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan
terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.41
Hukum pidana nasional adalah hukum yang didasarkan pada landasan ideologi
dan konstitusi negara, yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)42
yang berlaku secara nasional.
Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu proses memperbarui hukum positif
yang saat ini berlaku. Prosesnya hingga saat ini masih berlangsung yang dikemas
melalui legislasi. Memiliki hukum pidana produk sendiri bagi bangsa Indonesia
37
Ibid, 222. 38
Halim Rane. The Relevance of a Maqa>s{id Approach For Political Islam Post Arab
Revolutions, (Journal of Law and Religion, Vol. XXVIII, 2013), 493-494,. 39
Abu Isha>k As Sya>tibi>. al-Muwa>faqat fi> Ushul al-Syari>’ah, Beiru>t: (Da>r al-Kutub al-Ilmiyah.
2004), 223. 40
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010), 28-29. 41
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1999), 2. 42
M. Sularno, Syari‟at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, (Jurnal al-
Mawardi, Edisi XVI, 2006), 215.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
25
merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-
cita kemerdekaan. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
berdasarkan Pancasila. Hal ini merupakan garis kebijakan umum yang menjadi
landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia.43
Teori prasarat fungsional (imperatif-fungsional) Talcott Parsons dan
pengembangannya oleh pemikir lain dapat menjelaskan tentang urgensi
pembaharuan hukum serta tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.
Parsons merumuskan bahwa masyarakat mencakup sebuah sistem yang luas dan
elemen-elemennya mengisi empat fungsi dasarnya yaitu adaptasi (Adaptation),
melanjutkan tujuan (Goal), integrasi (Integration) dan memelihara norma-norma
(Laten Pattern Maintenance) atau pendekatan AGIL. AGIL yang dikembangkan
Parsons merupakan nomoteknis dalam mempertimbangkan fungsi-fungsi sistem
sosial. Masing-masing fungsi ini terkait dengan sebuah sub sistem. Sub sistem
ekonomi bertujuan untuk melakukan adaptasi; sub sistem politik bertanggung
jawab memberi definisi tujuan akhir; sub sistem kultural (agama dan sekolah)
bertugas untuk mendefinisikan dan memelihara norma-norma dan nilai; sub-
sistem sosial (termasuk hukum) bertugas sebagai integrasi sosial.44
Parsons
menempatkan hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem sosial yang lebih
besar. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (rule of
the game).
Harry C. Bredemeier mengembangkan teori yang dirumuskan Parsons
tersebut. Hukum menurut Bredemeier dapat digunakan sebagai pengintegrasi
sosial di dalam masyarakat. Keserasian antara warga masyarakat dengan norma
43 Qodri Abdillah Azizy, Membangun Integritas Bangsa, (Jakarta: Renaisan, 2004), 20-21. 44
Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory, (Homewood Illinois: The Dorsey
Press, 1975), 38.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
26
yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian dalam hubungan di dalam
masyarakat yang bersangkutan.45
Menjadi hal yang tidak logis apabila hukum
pidana yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan
norma-norma atau nilai-nilai yang yang dianut bangsa Indonesia. KUHP yang
merupakan peninggalan Belanda banyak yang tidak sesuai dengan nilai dan
budaya yang dianut bangsa Indonesia. Apabila hal ini terus dipaksakan berarti
terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat. Diperlukan hukum baru
yang sesuai dengan nilai yang dianut bangsa Indonesia yang dapat disebut hukum
Pancasila yang di dalamnya mengakomodasi hukum-hukum yang berasal dari
agama.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia perlu diimplementasikan
khususnya postulat moral kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap usaha
pembangunan perundang-undangan nasional. Demikian halnya dalam
pembangunan hukum pidana nasional yang mendasarkan pandangannya terhadap
prinsip filsafat Pancasila, dalam pengejawantahannya harus dijiwai nilai-nilai
Pancasila termasuk keseimbangan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang
dapat digali dari hukum-hukum agama. Perlu dilakukan penggalian terhadap nilai-
nilai hukum agama yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat
Indonesia. Hukum-hukum dari agama dapat dijadikan sumber dalam
pembangunan hukum pidana nasional.
Hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, dan sebagai salah
satu dari tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di samping hukum adat
dan hukum Barat, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam
45
Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,‟
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 152-153.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
27
pembangunan hukum pidana nasional. Sepanjang sejarah perjalanan hukum di
Indonesia, hukum Islam selalu memperteguh eksistensinya sebagai hukum tertulis
maupun tidak tertulis. Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional
mempunyai dua fungsi; 1) Sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi
pemeluk Islam saja.2)Sebagai ekspresi nilai-nilai yang akan berlaku bagi semua
warga Negara.46
Dari sisi pelaksanaannya, hukum Islam dapat digolongkan tiga macam;
1)Dapat dilaksanakan oleh individu secara langsung tanpa bantuan Negara, seperti
hukum-hukum di bidang peribadatan ritual. 2) Pelaksanaannya memerlukan
bantuan kekuasaan negara dalam kerangka administratif atau pelayanan, seperti
hukum keluarga. 3) Tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak ada campur
tangan negara, seperti hukum pidana.47
Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas
tentang perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan (terlarang) dan
yang harus dilakukan, ancaman pidananya, dan pertanggungjawabannya.
Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana menurut hukum pidana Islam
dapat berbeda penggolongan dan cara peninjauannya. Dilihat dari segi berat-
ringannya ancaman pidana, tindak pidana dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu
tindak pidana yang diancam pidana had (jari>mah hudu>d), tindak pidana yang
diancam pidana qis{as{-diyat (jari>mah qis{as{-diyat ) dan tindak pidana yang
diancam pidana ta‘zi>r (jari>mah ta‘zi>r). Ditinjau berdasarkan karakter khusus
tindak pidana, dapat dibagi menjadi tindak pidana masyarakat (jara>im al-jama>’ah),
46
Muhammad Julijanto, Implementasi Hukum Islam di Indonesia; Sebuah Perjuangan Politik
Konstitusionalisme, dalam Makalah Conference Procedings Annual International Conference on
Islamic Studies, (Mataram, September 2013), 78. 47 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM. Books, 2007), 14.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
28
tindak pidana perseorangan (jara>im al-afra>d), tindak pidana biasa (jara>im al-
adiyah) dan tindak pidana politik (jara>im as-siya>sah).48
Hukum Islam pernah diterapkan secara formal di Nusantara pada zaman
kerajaan-kerajaan Islam, hingga akhirnya dianulir oleh penjajah Belanda.
Sepanjang abad ke-19 di kalangan ahli hukum Hindia Belanda berkembang
pendapat bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam seperti dikemukakan oleh
Salomon Keyzer (1823-1868) dan dikuatkan oleh Lodewijk Williem Christian van
den Berg (1845-1927). Menurut Berg, hukum mengikuti agama yang dianut
seseorang. Jika telah memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku
baginya.49
Orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam
keseluruhan bidangnya sebagai satu kesatuan atau receptio in complex.
Hukum pidana Islam sangat penting untuk diperhitungkan dalam
pembangunan hukum pidana nasional sebagai sumber. Karena hukum pidana di
Indonesia menganut unifikasi, yakni hanya satu hukum, maka hukum pidana
Islam posisinya sebagai sumber materiil atau bahan yang disandingkan dengan
sumber atau bahan lain. Berbeda dengan hukum perdata khususnya hukum
keluarga yang menganut pluralisme hukum, hukum Islam di bidang perdata dapat
menjadi sumber formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang
belum memiliki bentuk tertentu atau masih berupa bahan sehingga belum bisa
diterapkan. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah
memiliki bentuk tertentu sehingga bisa langsung diterapkan.50
48
Abd al-Qa>dir Audah, al-Tasyri>’al-Jina>’i ‘al-Isla>mi>; Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wad{’i>, Jilid I,
(Beiru>t: Muasasah al-Risa>lah Litiba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’i, 1992), 79-99. 49
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-11, 2004), 242. 50
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari„ah, dalam Jurnal Hukum, No. 1
Vol. 14, Januari 2007, 15.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
29
F. Studi Terdahulu
Studi tentang Restorative Justice dan Pidana Islam telah dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya. Dari beberapa karya tersebut, penjelasan secara
utuh dan holistik yang menggambarkan Restorative justice dalam Hukum Pidana
Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam agaknya belum ditemukan. Namun
demikian, peneliti akan menguraikan karya-karya tersebut baik berupa desertasi,
buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.
Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana
Nasional Berbasis Ketentuan qis{as{-diyat dalam Hukum Pidana Islam,
merupakan Disertasi yang ditulis oleh Achmad Irwan Hamzami51
yang terdorong
untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep profil hukum
pidana nasional ke depan dengan mengkontribusikan hukum pidana Islam.
Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam seperti qis{as{-diyat secara
filosofis lebih menjanjikan dapat memberikan manfaat dan kepastian keadilan
sebagaimana tujuan utama dalam hukum pidana. Menurut hukum yang berlaku di
Indonesia, yang berhak melaksanakan proses pemidanaan adalah penguasa,
korban tidak dilibatkan. Akibat korban tidak dillibatkan, dalam pelaksanaan
pidana banyak menimbulkan masalah bagi korban, misalnya korban merasa tidak
mendapat perlindungan dari Negara dan tidak puas karena kerugian yang diderita
korban tidak tergantikan. Model pemidanaan demikian perlu untuk dikaji kembali.
Sebab untuk tindak pidana terhadap nyawa, keadilan tidak dapat terwujud tanpa
memperhatikan korban atau keluarganya, dan harmoni dalam masyarakat tidak
dapat dikembalikan.
51
Achmad Irwan Hamzami, Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana
Nasional Berbasis Ketentuan Qis{a>s{-Diyat dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang: PPs.
Universitas Diponegoro, Desertasi, 2015).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
30
Penyelesaian perkara pidana yang lebih adil adalah dengan cara
melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Model seperti
ini di Indonesia telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat, yaitu
musyawarah mufakat, yang dalam hukum pidana Islam berlaku untuk tindak
pidana qis{as{-diyat melalui perdamaian atau pemaafan (is{la>h{/al afwu{) dan mirip
dengan pendekatan restorative justice yang saat ini menjadi wacana global untuk
diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hanya saja tulisan ini terbatas
pada pendekatan qis{as{-diyat melalui perdamaian atau pemaafan (is{la>h{/al afwu {).
Kuat Puji Prayitno menyatakan bahwa Restorative justice merupakan
filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki
kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku criminal. Proses ini
sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai
pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. Restorative Justice menemukan
pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah
prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi
Korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang
mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan
masyarakat.
Kajian tentang Restorative Justice juga dapat ditelaah pada tulisan Ahmad
Ramzy52
pada tesis-nya yang berjudul Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam
Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana
Di Indonesia. Tesis ini mengkaji tentang pendekatan metode perdamaian (s{ulh{).
Di dalam perdamaian (s{ulh{) baik korban atau walinya ataupun washinya
52
Ahmad Ramzy, Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice
Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: PPs. Universitas
Indonesia, Tesis, 2012).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
31
(pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal
penggantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan diyat atau lebih
besar dari diyat. Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan
restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang dalam upaya penyelesaian
perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung
pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Proses
penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian sangat sesuai dengan ciri khas
bangsa Indonesia yaitu semangat musyawarah untuk setiap permasalahan pidana
dengan tujuan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium (obat terakhir)
bukan sebagai premium remedium (obat utama).
Kajian yang berkaitan dengan Disertasi ini, tentang Pidana Islam ditulis
juga oleh Ali Geno Berutu dalam Disertasi-nya yang berjudul Formalisasi Hukum
Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di
NAD). Penulis memaparkan seputar perdebatan syariah dalam negara disertai
pendapat para tokoh mengenai penerapan syariat,dijelaskan bahwa Islam adalah
ajaran yang lengkap dan sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia.
Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara agama dan dunia, inilah yang
dikenal dengan konsep Isla>m Di>n Wa ad-Daulah.
Untuk konteks negara Indonesia, ditinjau dari perspektif religio-politis,
syariat Islam dan negara adalah dua etnis yang sepanjang sejarah Indonesia
senantiasa selalu bergulat dengan pergumulan dan ketegangan abadi dalam
memposisikan relasi agama (syariat Islam) dan negara, anatara proyek
sekulerisasi, Islamisasi dan masyarakat. Penelitian ini fokus pada hukum pidana
Islam sebagai produk politik nasional secara umum dan produk hukum lokal, yang
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
32
lahir di Nangroe Aceh Darussalam. Formalisasi syariat Islam yang dimaksudkan
adalah upaya memasukkan syariat Islam ke dalam hukum Nasional. Produk
perundang-undangan local yang menjadi obyek penelitian adalah Qanun Nomor
12 Tahun 2003 tentang larangan Khamar. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat.
Dalam hasil penelusuran penelitian terdahulu tersebut berupa disertasi,
tesis, artikel jurnal maupun bentuk karya lainnya mengandung berbagai kritik,
analisis dan deskripsi dari para peneliti. Lebih lanjut penelusuran ini akan
diperkaya dengan berbagai artikel tambahan seperti yang terdapat dalam website
yang ada kaitanya dengan tema penelitian ini. Sebagaimana telah dilakukan
penelusuran terkait dengan tema: Restorative Justice dalam Hukum Pidana
Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam dapat diketahui secara jelas bahwa
penelitian ini adalah peneilitian yang bersifat aktual, khas, mengandung novelty,
dan secara spesifik belum ada pihak yang menelitinya.
G. Pendekatan dan Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan maqa>s{id (pendekatan filsafat
hukum Islam). Dalam menentukan pendekatan dalam penelitian tersebut
didasarkan atas alasan metodologis yang berkaitan dengan tema penelitian ini
yaitu terkait wilayah masalah, sifat masalah dan perspektif kajian ini. Pertama,
pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan maqa>s{id, yaitu melihat
maksud dan tujuan dari hukum pidana Islam. Kedua, terkait dengan wilayah
masalah ini mencakup penelitian peraturan perundang-undangan dan penelitian
empirik. Dalam hal ini wilayah perundang-undangan dan wilayah empirik digali
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
33
dari berbagai sumber dan juga data di lapangan. Secara definitif pendekatan
maqa>s{id dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sebuah sistem bisa tetap eksis manakala tetap menjaga atau
mempertahankan openness and self-renewal. Jasser Audah menawarkan dua
mekanisme dalam hukum Islam agar openness and self-renewal bisa terwujud.
Pertama, berubahnya sebuah hukum seiring dengan berubahnya cara pandang para
ahli hukum atau pengetahuannya tentang budaya. Kedua, philosophy keterbukaan
menawarkan diri sebagai mekanisme dari self-renewal dalam hukum Islam.53
Worldview adalah sebuah istilah yang sudah dikenal sejak seratus tahun
yang lalu dengan nama world outlook.54
Worldview adalah hasil atau produk dari
sekian jumlah faktor yang dapat membentuk seseorang memiliki pengetahuan
yang luas atau human cognition of the world. Worldview dihasilkan dari segala
sesuatu yang mengelilingi kita atau yang ada di sekitar kita, seperti agama,
lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi, bahasa dan sebagainya.
Berdasarkan tradisi, dasar atau asas dari al-‘urf dalam teori hukum Islam,
sama halnya berinteraksi dengan dunia luar (interaction with the outside world).
Dalam kaidah yang diusung oleh Hanafiyyah menegaskan bahwa al-ma‘ru>fu
‘urfan ka al-masyru>t{i syart{an. Kaidah ini telah disepakati oleh berbagai macam
sekolah hukum untuk bisa diterapkan di berbagai ranah masalah yang berkaitan
dengan hukum, selama tidak ada nash yang menyinggung hal tersebut. Sebagai
contoh standar dalam hal ini, sebagaimana yang dikenalkan oleh buku-buku usul
dalam hukum Islam adalah, nilai mahar wanita, penggunaan mata uang di setiap
53
Jasser Audah, Maqa>s{id al- Syari’ah Falsafah Li al-Tasyri>‘ al-Isla>mi> (London: The International
Institute Of Islamic Thought, 2007), 8. 54
Jasser Audah, Maqasid As Philoshophy Of Islamic Law (London: The International Institute Of
Islamic Thought, 2008),193.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
34
Negara, mengenakan penutup kepala atau tidak, penggunaan secara umum
beberapa kalimat berbahasa arab dan sebagainya.55
Tujuan dibalik melibatkan urf
dalam menentukan hukum Islam adalah untuk mengakomodasi atau menampung
berbagai macam keadaan orang yang berbeda dengan tradisi orang arab, yang
mana seluruh syariat pada awalnya diturunkan dan ditujukan untuk mereka pada
waktu itu. Tetapi kenyataannya, implikasi praktis (al-‘at{ar al’amaliyyah) dari al-
‘urf dalam kajian fiqh telah benar-benar dibatasi.
2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian Hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori
penelitian Yuridis Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan. Oleh karenanya
dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu
penelitian digolongkan sebagai data sekunder.56
Penelitian ini disebut juga sebagai
penelitian kualitatif.57
Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan
menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan relevansi sudut pandang
filsafat hukum Islam terhadap Restorative Justice dalam hukum pidana Islam.
Penelitian kualitatif tidak memakai alat ukur sebagaimana yang terdapat dalam
penelitian kuantitatif. Situasi dan kondisi lapangan juga bersifat alami, natural,
apa adanya dan tidak dibuat-buat.58
Kondisi dan situasi penelitian yang alami dan
natural merupakan salah satu ciri yang dominan dalam jenis penelitian ini, sebab
fakta yang dihadapi bersifat kompleks, dinamis dan variatif.
55
Mas’oud Ibnu Mu>sa> Flousi>, Madrasah al-Mutakallimi>n (Riya>dh: Maktabah al-Rush, 2004), 354. 56
Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali,
2003), 23-24. 57
R. Bogdan dan Steven Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (John Wiley &
Sons, 1984), 42. 58
Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif‟, Equilibrium 5, no. 9 (2009), 8.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
35
Patton sebagaimana dikutip oleh Poerwandari menyebutkan bahwa desain
situasi alamiah dalam penelitian kualitatif merupakan studi yang berorientasi pada
penemuan (discovery oriented). Studi alamiah ini sangat berbeda dengan studi
eksperimental yang secara ideal diarahkan pada upaya peneliti untuk secara penuh
mengendalikan konteks penelitiannya.59
Ciri mendasar lain dalam penelitian
kualitatif selain data yang dikumpulkan bersifat alamiah, posisi peneliti sebagai
alat penelitian. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat strategis
mengingat posisi peneliti sebagai alat utama pengumpul data.
Adapun penentuan jenis penelitian ini disesuaikan dengan sifat alamiah
masalah penelitian yaitu persentuhan antara nilai-nilai Restorative Justice dalam
hukum pidana Islam dengan hukum pidana Nasional. Selanjutnya alasan
dipilihnya pendekatan kualitatif sebab penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran atau deskripsi yang komprehensif yang terkait sudut pandang filsafat
hukum Islam tentang Restorative Justice dalam hukum pidana Islam dengan
kondisi efektifitas hukum pidana, kondisi aparat penegak hukum, serta peran serta
masyarakat. Adanya peran serta dan keterlibatan masyarakat yang berkaitan
dengan penerapan Restorative Justice dalam konsep hukum pidana Islam terhadap
pembaruan hukum pidana nasional, merupakan hal yang sangat penting untuk
terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi. Metode ini
disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.
Metode deskripsi adalah metode penelitian dengan menggambarkan pada subjek
59
E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia, 3rd
ed. (Jakarta: LPSP3,
2009), 44.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
36
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat atau lainnya) yang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak sebagaimana adanya.60
Adapun tujuan metode deskripsi ini
adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki.61
Penentuan metode deskripsi ini didukung dengan alasan dan
penerapannya. Adapun alasan pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan
penelitian, yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk dan kontribusi nilai-nilai
Restorative Justice dalam hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum pidana
Nasional. Sedangkan penerapannya dengan cara menganalisis data-data kualitatif
lapangan, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data yang
peneliti inginkan.
4. Bahan Hukum
Sumber Bahan Hukum sebagai epistemologi dalam penelitian menempati
urgensitas tinggi karena disinilah letak kekayaan Bahan Hukum yang akan
diperoleh sehingga bisa menghasilkan penelitian yang sempurna. Adapun sumber
Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Bahan yang
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi62
teks-teks Al-Qur‟an dan
Al-Hadits yang memuat pembahasan tersebut. Bahan hukum yang dimaksud
60
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1991), 73-76. 61
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63. 62
Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri (Jakarta; Ghalia
Indonesia,1990),12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
37
dihimpun melalui telaah kepustakaan (library research) yang diklasifikasikan atas
sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.63
1. Sumber bahan hukum primer; Merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada
penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan pertama ialah al-Qur‟an
dan al-Hadits.
2. Sumber bahan hukum sekunder; Suatu bahan pustaka yang berisi
informasi tentang bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal,
majalah, naskah, dokumen dan sumber literature lainnya. Karena dalam
penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar
yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.64
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumenn resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.65
3. Sumber Bahan Hukum tersier; merupakan Bahan Hukum penunjang,
mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber
bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi: kamus,
ensiklopedi dan lain- lain.66
63
Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat. (Yogyakarta: Kanisisus,
1992). 64
Sarjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif‟ (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 24. 65
Ibid, 141. 66
Amirudin dan Zainal Asikin,.. 30.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
38
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk menganalisa bahan hukum, Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik kepustakaan (Library research). Dalam hal ini
berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan obyek pembahasan,
serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas yaitu mengenai
Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.
Untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka
bahan hukum yang didapatkan dari Al-Quran, hadits, kitab, buku, jurnal, artikel,
penelitian-penelitian, dan literatur yang terkumpul, kemudian dilakukan analisis
secara komperhensif sebagai upaya menemukan solusi yang terbaik terhadap
peran restorative justice yang ada dalam hukum pidana Islam.
6. Teknik Analisis
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dengan
menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan bahan hukum dari sumber
Bahan hukum dan mengolah bahan hukum kemudian dianalisis dengan
pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti menggunakan
metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan persaman-
persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja.
Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan
pandangan orang, grup, atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, terhadap
peristiwa atau ide-ide.67
67
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
39
7. Instrumen Penelitian
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik pada tahapan pertama,
mendapatkan data dasar sampai pada tahapan membandingkan, merupakan data
yang bersifat kualitatif. Oleh sebab itu instrumen utama dalam penelitian ini
adalah peneliti sendiri.68
Data tersebut didapatkan melalui observasi. Untuk
menjaga keobjektifan, pengamatan juga dilakukan oleh pihak-pihak yang
memanfaatkan lembar observasi. Untuk melengkapi data, akan dilakukan
wawancara dengan pihak-pihak terkait.69
Adapun jenis data penelitian ini meliputi dokumentasi data sekunder dari
berbagai buku, jurnal dan karya ilmiah. Rincian jenis data tersebut di ataranya
adalah:
a. Memahami makna dan nilai Restorative Justice dalam hukum pidana
Islam.
b. Relasi antara Restorative Justice dalam hukum pidana Islam terhadap
pembaharuan hukum pidana Nasional.
c. Sejarah hukum pidana Islam dan hukum Islam di Indonesia.
d. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kontribusi hukum pidana Islam di
Indonesia.
e. Bentuk-bentuk kontribusi hukum pidana Islam di Indonesia.
8. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
68
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001),
175. 69
Nusa Putra, Research and Development, Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar,‟
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 175-177.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
40
a. Mengumpulkan seluruh data hasil pengamatan berupa catatan
lapangan, dan catatan diskusi.
b. Melakukan analisis pertama untuk memilah data ke dalam beberapa
kategori.
c. Melakukan analisis kedua di dalam masing-masing kategori.
d. Melakukan proses sintesis yaitu mengolah keseluruhan data untuk
merumuskan kategori tersebut.
e. Pembuatan simpulan akhir.
Namun secara garis besar proses analisis data dilakukan melalui tiga
tahapan, yaitu (1) deskripsi. (2) formulasi.(3) Interpretasi. Jika digambarkan
sebagai berikut:
9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam proses menguji keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa
teknik agar data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dengan cara
diantaranya adalah:
a. Ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan adalah mencari
kedalaman data sehingga diadakan pengamatan yang teliti dengan
berkesinambungan sampai muncul perilaku yang diharapkan.
Data Reduction
Data Collection Data Display
Conclusion
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
41
b. Triangulasi. Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi
yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui
sumber yang lainnya. Triangulasi dilakukan melalui wawancara,
observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak
langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa
kelakukan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut
diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduannya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam
memperoleh data primer dan sekunder, observasi, dan interview.
H. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab di antaranya
adalah: Bab I membahas tentang; (a) Latar belakang masalah latar belakang
masalah yang meliputi problem akademik, kebutuhan pemecahan ilmiah, urgensi
penelitian dan aktualisasi penelitian. (b) identifikasi dan batasan masalah meliputi
berbagai masalah penelitian yang muncul agar wilayah penelitian jelas dan
terarah. (c) rumusan masalah berguna untuk memperjelas persoalan penelitian. (d)
tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Adapun jawaban dari
rumusan masalah akan disajikan ke dalam bab II, bab III dan bab IV sesuai
dengan proporsi sistematikanya masing-masing. (e) kegunaan penelitian. (f)
kerangka teoritik,(g) penelitian terdahulu,(h) metode penelitian, (i) sistematika
pembahasan.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
42
Bab II membahas tentang isi konsep teoritis yang berkenaan dengan
masalah penelitian dan istilah-istilah konseptual yang terdapat di dalam kajian
perspektif filsafat hukum Islam tentang restorative justice dalam hukum pidana
Islam. Konsep teoritis ini digunakan sebagai wawasan konseptual tentang masalah
penelitian serta instrumen dalam memahami dan menganalisis data penelitian.
Adapun konsep tersebut merupakan kebutuhan langsung dalam kajian penelitian
sebagaimana penelitian-penelitian pada umumnya.
Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian beserta analisisnya untuk
menjawab rumusan masalah. Bab ini akan menyajikan pemaparan secara
deskriptif tentang fakta Restorative justice yang ada dalam masyarakat.
Bab IV menjelaskan tentang analisis data dari jawaban rumusan masalah.
Pada bab ini, teori-teori yang dikemukakan pada bab II digunakan untuk
menganalisa kasus-kasus yang dipaparkan pada bab ini, sehingga bisa ditemukan
kesesuaian antara teori dan kasus yang ada.
Bab V berisi tentang penutup. Adapun di bab V ini disajikan kesimpulan
yang disertai dan dilengkapi mengenai penjelasan terhadap implikasi teori,
keterbatasan studi serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
43
BAB II
KEADILAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
A. Filsafat Hukum Islam
1. Pengertian Filsafat Hukum Islam
Para ahli mempunyai definisi yang sangat beragam mengenai apa itu
filsafat hukum Islam.70
Hal ini terjadi, karena filsafat hukumIslam dalam tradisi
keilmuan Islam merupakan disiplin baru. Dalam pembidangan ilmu keislaman
tradisional, filsafat hukum belum dikenal sekalipun dalam beberapa hal, ia
mempunyai kemiripan dengan usul fikih. Karena masih termasuk disiplin baru,
filsafat hukum Islam masih dalam proses pencarian bentuk bakunya. Ia tidak
seperti filsafat Islam yang sudah mempunyai bentuk baku.
Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakika hukum Islam,
sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan
manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.71
Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia
merupakan filsafat yang diaplikasikan pada obyek tertentu, yaitu hukum Islam.
Karena itu filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam
secara metodisdan sistematis sehinga mendapat keterangan yang mendasar, atau
menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.
70
Keragaman ini terjadi disebabkan masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah
filsafat/falsafah sama dengan hikmah? Bagi kalangan yang menyamakan filsafat/falsafah sama
dengan hikmah, filsafat hukum Islam diidentikkan dengan ḥikmah al-aḥkām atau asrār al-aḥkām
(rahasia-rahasia hukum). Bagi kalangan yang membedakan filsafat dengan hikmah, mereka
mendefenisikan filsafat hukum Islam sebagai upaya pemikiran manusia secara maksimal untuk
memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Tuhan, dengan tidak
meragukan subtansi hukum Islam itu sendiri. Sementar hikmah didefenisikan sebagai anugerah
atau keutamaan yang ada di dalam nash, yang itu sudah digariskan oleh sang pembuat hukum:
Allah SWT. Lihat Ali> Ahmad al-Jurzāwῑ, Ḥikmah al-Tasyrῑ’ wa Falsafatuhu> (Bairu>t: Dār al-
Fikr, tth), I, 5-7. 71
Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 55.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
44
Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara
ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum
Islam.72
Filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan
rumusan lainFilsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia,
dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya,
atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, danmemelihara
hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksuddan tujuan Allah menetapkannya di
muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat
ini hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam
(saalihun likulli zaman wa makan).
Dari beberapa definisi yang dianggap representatif dan komprehensif dari
definisi yang diberikan oleh para ahli, maka penyusun mengambil pemahaman
bahwa, filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu,
yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan
pada hukum Islam, dimana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam
secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar.73
Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat
(ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum
Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, radikal dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan filsafat sebagai instrumen
analisis, maka filsafat hukum Islam tidak bisa lepas dari tiga komponen, yaitu: apa
ontologi hukum Islam; bagaimana epistemologi hukum Islam; serta aksiologi
hukum Islam.
72
Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan
dan Penerbitan, FH UII, 1984), 2 73
Fathurrrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, ke-1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 37.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
45
Sebagai sebuah ilmu, filsafat hukum Islam mempunyai dua macam objek,
yaitu objek materiil (fῑ zāhirihi>) dan objek formal (fῑ bāt}inihi>).74 Objek
materiilnya adalah sesuatu yang dijadikan penyelidikan, analisis, dan penalaran.
Dalam hal ini yang menjadi objek mareriilnya adalah hukum Islam. Dengan kata
lain, hukum Islam diselidiki, dianalisis, dan dinalar dengan menggunakan
instrumen filsafat. Hukum Islam sebagai objek analisis, dan filsafat sebagai pisau
bedah analisisnya. Adapun objek formalnya adalah sudut pandang untuk
memahami objek materiil, yaitu ilmiah, menyeluruh (komprehensif), rasional,
radikal, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan tentang hukum Islam.
Artinya dalam mengkaji dan menganalisa hukum Islam, maka dilakukan dengan
cara-cara rasional, radikal, menyeluruh dan sistematis.
Secara garis besar filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas utama:
tugas kritis, dan tugas konstruktif‟.75
Pertama, tugas kritis. Seperti diketahui,
filsafat adalah ilmu kritis.76
Tugas kritis dalam konteks hukum Islam adalah
mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah atau dianggap mapan
di dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawabanyang tidak
memadai, sekaligus ikut andil dalam mencari jawaban yang benar dan relevan.
Selain melakukankritik internal di dalam hukum, filsafat juga melakukan kritik
eksternal, yaitu kritik ideologi. Artinya, dalam proses penemuan atau
pembentukan hukum Islam jangan sampai ada bias-bias ideologi atau kepentingan
tertentu dari seorang ahli hukum.
Kedua, tugas konstruktif. Tugas konstruktif di sini adalah membina,
membangun, mempersatukan serta menyelaraskan cabang-cabang hukum Islam
74
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, cet ke-12 (Jakarata: PT. Grafindo Parsada, 2013), 1. 75
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Piara, 1993), 21. 76
Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 20.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
46
dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan kata
lain, filsafat berfungsi untuk mengkonstruks bangunan suatu hukum dalam hukum
Islam, baik itu dalam aspek ontologi, epistemologi serta aksiologinya menjadi satu
kesatuan yang utuh, sistematis, dan runut. Berikut akan kami paparkan uraian dari
ketiga instrument tersebut:
a. Ontologi Hukum Islam
Secara bahasa ontologi berasal dari bahasa Yunani, on sama dengan being,
dan logos sama dengan logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being
(teori tentang keberadaan sebagai keberadaan).77
Objek telah ontologi adalah
sesuatu yang ada. Ia berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan,
menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.78
Dengan demikian, ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks
hukum, ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum.
Hakikat sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu.
Sebelum menjelaskan hakikat hukum Islam, maka di sini harus
diterangkan terlebih dahulu beberapa konsep yang berkaitan dengan hukum Islam.
Seperti diketahui, hukum Islam disebut dengan beberapa nama yang masing-
masing nama tersebut menggambarkan ciri dan karakteristik tertentu. Dengan
memahami nama-nama tersebut, kemudian bisa diketahui apa itu hakikat
(ontologi) hukum Islam. Nama-nama yang dimaksud adalah (1) syarī'ah, (2) fikih,
dan (3) hukum syar'ī.
77
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu…., 132. 78
Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu: Positivisme, Post-Positivisme, dan Post-modernisme
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2012), 57.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
47
Pertama, syarī’ah/syir’ah yang secara leksikalmempunyai makna jalan
menuju ke mata air (mā yusrau’ ilā al-māi’),79 yang mempunyai konotasi
keselamatan. Sementara dalam terminologi, kata syarī’ah dipakai dalam dua
pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas
syarī’ah sama dengan al-dīn yaitu keseluruhan norma agama Islam yang meliputi
aspek doctrinal (aqīdah) dan aspek praktis („amaliyah). Dengan pengertian ini,
syariah adalah sebuah sistem normatif‟ Islam yang sangat komprehensif.80
Ia
mencakup persoalan akidah, hukum, doktrin, ritual, interaksi dan hubungan
internasional.
Sementara dalam arti sempit syariah hanya merujuk kepada aspek praktis
(„amaliyah), tingkah laku konkret manusia saja.81
Dengan demikian, ketika
disebut hukum Islam, maka yang dimaksud adalah syariah dalam arti sempit.
Syariah merupakan ketentuan-ketentuan universal yang terdapat dalam teks (nash)
al-Qur‟an dan Sunah. Dengan demikian syariah adalah kewenangan ilahi yang di
dalamnya tidak ada intervensi manusia. Dari sini, yang membuat syariah (syari‟)
adalah Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad.
Kedua, Fikih; yangmempunyai pengertian adanya intervensi nalar
manusia di dalamnya. Secara bahasa fikih adalah al-fahm,82
yakni pemahaman
yang mendalam mengenai sesuatu. Fikih adalah istilah lain yang digunakan untuk
menyebut hukum Islam. Sebagai sebuah istilah, fikih dipakai dalam dua arti:
Pertama, fikih dalam arti ilmu hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan
79
Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Ibn Kaṡīr (Bairu>t: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), II, 61. 80
Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal (Jakarta: Sembarani
Aksara Nusantara, 2003), 194. 81
Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa Min „Ilm Al-Usul Karya Al-
Gazzali [450-505 H / 1058-1111 M] (Yogyakarta: Disertasi, 2000),118-121. 82
Aṭhā bin Khalīl Abū Ar-Rastah, Taisīr al- Uṣūl ilā al- Uṣūl: Dirāsah fī Uṣūl al-Fiqh, cet. 3
(Bairut: Dārul Umat, 2000), 6.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
48
jurisprudence. Fikih ketika dimaknai sebagai ilmu hukum mempunyai pengertian
sebagai cabangstudi yang mengkaji hukum Islam. Kedua, istilah fikih dipakai
dalam arti hukum itu sendiri, atau paralel dengan law dalam bahasa Inggris.83
Di
sini, fikih dimaknai sebagai himpunan normaatau peraturan yang mengatur
tingkah laku konkret baik berasal dari al-Qur‟an, Sunnah, maupun dari hasil
ijtihad ahli hokum Islam.
Ketiga, Hukum Syar‟i Hukum berasal dari bahasa Arab yang secara
harfiah mempunyai arti yang beragam: keputusan, ketetapan, peraturan,
ketentuan, perintah, dekrit, dan norma.84
Sementara menurut para uṣūlliyyīn,
hukum syar‟i didefinisikan sebagai titah ilahi (khithābullah) yang tertuju kepada
perbuatan manusia yang berisi tuntutan, penetapan atau pemberianalternatif.85
Definisi tersebut mengandung dua hal, pertama, bahwa hukum itu adalah titah
ilahi yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah
lakunya. Kedua, bahwa hukum yang merupakan titah ilahi itu berisi tuntutan,
alternasi (pemberian pilihan, dan penetapan).
Dari ketiga konsep di atas, sebenarnya ada tiga unsur yang berperan dalam
hukum Islam, yaitu teks sebagai perwujudan dari wahyu Tuhan; akal atau nalar
dari seorang mujtahid; serta realitas yang hidup yang dihadapi, dimana hukum itu
akan diterapkan. Dengan demikian, menyatakan hukum Islam sebagai kumpulan
ketentuan Tuhan yang tertulis dalam teks-teks Al-Qur‟an dan Sunnah adalah
sebuah tindakan simplikasi. Hukum Islam, tidak lain adalah perpaduan wahyu
Tuhan dan pemikiran manusia di dalamnya. Akal manusia ketika dihadapkan
83
Aḥmād Musṭafā az-Zarqā’, Al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihi al-Jadīd (Bairut: Dār al-Fikr, 1967), I,
54-55. 84
Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam...,126. 85
Aṭhā bin Khalīl Abū Ar-Rastah, Taisīr al- Uṣūl ilā al- Uṣūl…, 9.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
49
dengan realitas yang hidup, yang berbeda dengan realitas yang dihadapi oleh
Nabi, berusaha mendialogkan itu dengan ketentuan-ketentuan teks (nash)wahyu.
Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa ontologi hukum Islam
adalah interelasi antara teks (nash/naqal), akal (ra’yu), dan realitas yang hidup
(waqā’i). Interelasi antara teks (nash), akal, dan realita, mempunyai dua bentuk
paradigma dalam sejarah hukum Islam. Yaitu antara paradigma struktural dan
paradigma fungsional.86
b. Epistemologi Hukum Islam
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti
pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu, atau teori. Dengan
demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan (theory of
knowledge). Sedangkan secara terminologi, epistemologi merupakan cabang
filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, cara
mendapatkannya, serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah
pengetahuan serta bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya.87
Para ahli mengatakan ada tiga problematika yang dibahas dalam
epistemologi, yaitu a) sumber pengetahuan; b) metode untuk memperoleh
pengetahuan; dan c) validitas Pengetahuan.88
Maka ketika dikaitkan dengan
hukum Islam, epistemologi hukum Islam juga berbicara mengenai sumber hukum
Islam, metode penggalian hukum Islam, dan validitas hukum Islam. Berikut kami
86
Paradigma struktural sangat erat kaitannya dengan struktur, dimana dalam struktur tersebut teks
mempunyai posisi yang sangat penting, dan sangat mendominasi. Berbeda dengan paradigma
fungsional, dimana antara teks, nalar, dan realitas saling berdialog dan berdialektika. Lihat Al
Yasa Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, cet. ke-
1 (Jakarta: Kencana, 2016), 329. 87
J. Sudarminta, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan, cet ke-6 (Yogyakarta,
Kanisius, 2008), 18. 88
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
50
uraikan di bawah ini:
1). Sumber Hukum Islam
Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari maṣādir al-aḥkām oleh
ulama fikih dan usul fikih klasik; atau al-adillah al-syar’iyyah oleh ulama
sekarang. Yang diartikan sebuah wadah yang merupakan tempat penggalian
norma-norma hukum dan ini hanya berlaku pada Al-Qur‟an dan Sunnah.89
Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sumber mempunyai arti asal
sesuatu. Jadi, sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai asal atau tempat
pengambilan hukum Islam.
Pertama, Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai
hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai
pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta media ber-taqarrub kepada Allah
dengan membacanya.90
Dalam hukum Islam, al-Qur‟an adalah sumber dari segala
sumber hukum. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin mengenai
kedudukan al-Qur‟an sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam.
Bukti yang menyatakan bahwa al-Qur‟an merupakan sumber dan dalil hukum
yang utama dan pokok adalah al-Qur‟an itu sendiri. Dalam merumuskan semua
hukum, jika menghendaki kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman
kepada al-Quran. Sebagai sumber, hukum dan undang-undang yang dibuat
manusia tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah hukum al-Qur‟an.
89
Fathurrrahman Djamil…, 80. 90
Abdul Wahāb Khālla>f, Ilmu Uṣūl al-Fiqh (Indonesia: Haramain, 2004), 23.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
51
Kedua, Sunnah adalah suatu laporan mengena masa lalu, khususnya
laporan seputar Nabi, baik itu menyangkut perkataanya, perbuatannya, dan
persetujuan diam yang ditunjukinya (taqrīr).91
Selain al-Qur‟an, Sunnah adalah
salah satu sumber tempat penggalian hukum Islam. Selain sebagai sumber hukum,
al-Qur‟an juga berfungsi sebagai penguat terhadap teks, penjelas, penafsir,
mengkhususkan, serta membuat hukum baru, yang tidak ada dalam al-Qur‟an.92
Pertanyaan yang muncul dari segi epistemologi adalah mungkinkah kita
mengetahui masa lampau?93
Harus diakui, pengetahuan kita terhadap masa lalu
adalah pengetahuan yang terbatas. Dengan arti, tidak mungkin kita bisa
menghadirkan kembali masa lalu secara empiris, karena masa lalu itu telah hilang
dan lenyap. Sekalipun pengetahuan terhadap masa lalu sangat terbatas, bukan
berarti merelatifkan semua tentang masa lalu, yang nota-benenya Sunnah adalah
bagian dari masa lalu itu. Untuk itu, para uṣūlliyyi>n berpendapat pastilah ada dari
masa lalu itu yang bisa diketahui secara pasti. Atas dasar itu, mereka membedakan
pengetahuan masa lalu itu kepada pengetahuan yang bersifat pasti dan final
(qath’ī) dan pengetahuan yang bersifat tentatif dan relatif (zhannī).94
Dengan begitu, para uṣūlliyyīn berpendapat bahwa pengalaman inderawi
bukan satu-satunya sumber andalan pengetahuan.95
Menurut mereka kesaksian
atau laporan juga bisa dijadikan sumber dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan
91
Muhammad Khuda>ri> Baek, Tārīkh al-Tasyrī‟ al-Islāmīy (ttp, Haramain, tth), 35. 92
Wahbah az-Zuhailīy, Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 37-39. 93
Syamsul Anwar…, 272. 94
Abdul Wahāb Khāllaf…,43. 95
Dalam epistemologi, ketika berbicara mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan, ada
yang disebut aliran empirisme. Aliaran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan diperoleh
dengan perantara panca indra. Panca indra memperoleh kesan-kesan yang dialaminya di alam
nyata. Maka menurut empirisme, pengetahuan terdiri dari penyusunan dan pengaturan kesan-
kesan yang dialami oleh panca indra tersebut. Lihat Harun Nasution, Falsafat Agama, cet ke-9
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), 8.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
52
sejarah umpamanya, kesaksian serangkaian orang yang disebut dengan rawi
dalam teori ‘ulūm al-ḥad>iṡ dan pembentukan sanad yang menghubungkan kita ke
masa lalu menjadi jembatan yang memungkinkan kita memiliki pengetahuan
tentang masa silamitu. Untuk itu dalam usul fikih, ketika membahas sunnah ada
dua kategori laporan: laporan mutawatir dan laporan ahad.96
Laporan mutawatir
merupakan laporan yang dialirkan melalui banyak jalur yang sedemikian rupa
sehingga tidak memungkinkan terjadinya persekongkolan dalam kebohongan.
Sementara laporan ahad (tunggal) adalah laporan yang disampaikan melalui satu
jalur atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Laporan mutawatir secara
epistemologis menimbulkan pengetahuan (ilmu). Mutawatir sendiri berarti
bertubi-tubi atau beruntun (at-tatābu’). Jadi keberuntunan serta banyaknya jalur
dan sumber laporan tersebut menimbulkan kepastian tentang kebenaran isinya
(qaṭ‟ī). Laporan mutawatir merupakan laporan yang kebenaran isinya diketahui
berdasarkan laporan itu sendiri, tanpa tergantung kepada atau ditentukan oleh
verifikasi data. Adapun laporan ahad (tunggal) tidak menghasilkan pengetahuan
pasti (qaṭ‟ī), melainkan hanya menimbulkan pengetahuan tentatif (zhannī), dan ini
merupakan bagian terbesar dari laporan masa silam di seputar Nabi.97
2). Metode Penemuan Hukum Islam
Berdasar ontologi di atas, bahwa hukum Islam itu adalah interrelasi
antara teks, nalar, dan realita. Maka dalam hukum Islam, hukum itu tidak dibuat,
melainkan ditemukan, dan para mujtahid tidak menetapkan hukum, akan tetapi
96
Mayoritas ulama (jumhūr al-‘ulama>’) membagi Sunnah dilihat dari aspek sanadnya menjadi
dua: mutawatir dan ahad. Adapun klasifikasi yang dibuat oleh kalangan Hanafiyah membagi
Sunnah kepada tiga kelompok: mutawatir, masyhur, dan ahad. Masyhur dalam klasifikasi
Hanafiyah masuk kepada ahad dalam klasifikasi Jumhur. Lihat Wahbah az-Zuhaily, Uṣūl al-Fiqh
al-Islāmīy (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986, I), 451. 97
Wahbah az-Zuhaily…, 451- 455.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
53
menemukan hukum.98
Untuk itu, metode penemuan hukum Islam atau dalam usul
fikih disebut dengan ṭarīqah istinbāṭ al-aḥkām dan ṭarīqah istidlāl al-aḥkām99
mempunyai tidak metode ijtihad: a) metode bayānī (linguistik); b) metode ta’lilī
„(kausasi), c) metode istiṣlāhī (teleologi).100
Tiga metode ini tidak menunjukkan
hierarki, melainkan hanya sekadar klasifikasi. Dengan demikian, tidak bisa
dikatakan bahwa metode yang pertama lebih baik dari metode yang kedua, atau
sebaliknya dan seterusnya. Tiga metode inilah yang dipergunakan dalam
menemukan dan membentuk peradaban fikih dari masa ke masa. Berikut kami
uraikan tentang ketiganya:
a). Metode Bayānī (Linguistik)
Metode ijtihad bayānī adalah upaya penemuan hukum melalui
interpretasi kebahasaan. Metode ini diidentikkan dengan penggunaan nalar ijtihad
yang lebih memprioritaskan redaksi teks dari pada substansi teks, sehingga
konsentrasi metode ini lebih berkutat di seputar penggalian pengertian makna
teks. Dalam bayānī, redaksi teks dalam hal ini teks-teks syariah yang berupa al-
Qur‟an dan Hadis adalah sesuatu yang final, kaidah-kaidah kebahasaan sangat
dominan di dalam metode ini. Dalam metode ini, fokus kajiannya diarahkan
kepada empat segi: a) bagaimana tingkat kejelasan pengertian makna teks hukum;
98
Syamsul Anwar…, 305. 99
Al Yasa Abu Bakar membedakan antara istinbāṭ al-aḥkām dan istidlāl al-aḥkām. Bahwa
istimbāth itu pemahaman dan penafsiran secara deduktif, sementara istidlāl adalah pemahaman
dan penafsiran secara induktif. Lihat Al Yasa Abubakar, Metode Istislahiah..., 1. 100
Para ahli hukum Islam modern membagi metode/penggalian hukum Islam menjadi tiga seperti
disebutkan di atas. Ada sebagian ahli yang mempunyai klasifikasi masing-masing; Muhammad
Abu Zahra membagi kepada dua metode: 1) metode literer (ṭuruq al-lafẓiyah), dan 2) metode
maknawiyah (ṭuruq ma‟nawiyah); Syamsul Anwar membagi kepada tiga metode: a) bayānī
(lingusitik), b) ta‟lîlî (dibagi kepada dua lagi: metode qiyasi dan metode istislahi), dan c) taufîqi
(sinkronisasi). Lihat Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dar al-fikr al-„Arabi, tth),
hlm. 115 dan Syamsul Anwār. Muzakkirah fī Uṣūl al-Fiqh II (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Suka, 2012), 13.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
54
b) pola-pola penunjukan kepada hukum yang dimaksud; c) luas sempitnya
cakupan pernyataan hukum; dan d) bentuk formula taklif dalam pernyataan
hukum.101
Dalam peradaban Islam, teks sangat penting peranannya.102
Metode ini
mempunyai kelemahan ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan
baru, yang dalam teks belum atau tidak diatur sama sekali. Seperti adagium yang
terkenal dari para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa teks-teks hukum itu
terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas (an-nuṣuṣ
mutanāhiyah wa al-waqā‟i ghairu mutanāhiyah). Maka untuk menjembatani itu,
dalam hukum Islam ada namanya metode ta‟lîlî (kausasi).
b). Metode Ta’li>li> (Kausasi)
Metode ta’lili > adalah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang yang
ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan causa legis (illat) yang
digali dari kasus nas kemudian diterapkan kepada kasus baru tersebut.103
Dalam
metode itu fokus kajiannya adalah subtansi teks, berupa illat. Illat itu sendiri
didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu keadaan, yang relatif dapat diukur, dan
mengandung relevansi, kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan
hukum.104
Metode ini berdasarkan atas anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang
diturunkan oleh Allah terhadap manusia mempunyai alasan logis (nilai hukum)
dan hikmah yang dicapainya; Allah tidak mungkin menurunkan ketentuan-
101
Syamsul Anwār…, 14. 102
Nasr Ha>mid Abu >Zayd menyatakan bahwa; peradaban Arab Islam adalah peradaban teks. Inilah
salah satu yang membedakan hukum Islam dari hukum Barat. Hukum Barat menggali hukum
dari tingkah laku masyarakat, sementara hukum Islam selain mempertimbangkan tingkah laku
masyarakat, juga menggali hukum dari teks-teks sebagai kerangka rujukannya. Metode bayānī
dianggap sebagai metode yang paling awal dari dua metode lainnya, metode ini dipergunakan
oleh para mujtahid hingga abad pertengahan dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum.
Lihat Nasr Ḥāmid Abū Zayd, Mafhūm al-Naṣ Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Bairūt: Al-Markaj
as-Saqāfi al-„Arabī, 2000, cet. ke-5), 9. 103
Syamsul Anwar…, 342. 104
Wahbah az-Zuhaily…, 646.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
55
ketentuan secara sia-sia tanpa ada hikmah dibaliknya.105
c). Metode Istiṣlāhī (Teleologis)
Metode istiṣlāhī adalah metode penggalian hukum dengan bertumpu
pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur‟an dan Hadits.
Atau metode ini secara sederhana disebut sebagai metode yang dalam penggalian
hukum menjadikan tujuan hukum (maqāṣid as-syarī’ah) sebagai pertimbangan
utama.106
Dengan demikian, kemaslahatan umum merupakan tujuan dari hukum
Islam. Para ulama usul fikih mendefinisikan maslahat sebagai bentuk apresiasi
dari ketertiban hukum dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat dan
menghindar dari kerusakan (min taḥqīq al-maslaḥah au jalbi maḍarrah). Akan
tetapi harus digarisbawahi bahwa tidak semua kemaslahatan dapat dijadikan
sebagai dasar penetapan hukum. Kemaslahatan yang sah dijadikan sebagai tujuan
dari penggalian hukum adalah kemaslahatan yang didukung oleh nash, dan selaras
dengan semangat syara‟ secara umum.107
3). Validitas Pengetahuan
Problem epistemologi yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan itu
105
Ta‟lili (kausasi), merupakan metode dengan corak deduktif, dimana untuk menemukan hukum
baru (premis minor) harus berpatokan kepada premis umum, yaitu berupa hukum asal. Di sini
terjadi perbedaan antara Al-Ghaza>li> dan As-Sya>tibi>. Bagi Al-Ghaza>li>, premis minor (hukum
cabang) itu sifatnya pasif, karena dialah yang dicari status hukumnya. Ini bisa dimaklumi, karena
qiyas-nya Ghazali dipengaruhi oleh silogismenya Aristoteles. Sementara bagi Syatibi, premis
minor itu harus aktif, dia harus berdialektika dengan premis mayor. Lihat Syamsul Anwar,
Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa> Min ’Ilmi al-Us}u>l Karya Al- Ghazali [450-505 H
/ 1058-1111 M] (Yogyakarta: Disertasi, 2000), 118-121. 106
Syamsul Anwār…, 46-47. 107
Para ahli membagi maslahat itu kepada tiga kategori: Pertama, maslaḥah mu‟tabarah, yaitu
maslahat yang diakui legalitasnya dalam syariat, baik langsung maupun tidak langsung; Kedua,
maslaḥah mulghah, yaitu maslahat yang legalitasnya ditolak oleh syariat; dan Ketiga, maslaḥah
mursalah, yaitu maslahat yang tidak ada legalitasnya, apakah dia ditolak atau diterima oleh
syariat. Lihat Wahbah az-Zuhaily, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986), II,
752-754.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
56
diuji kebenarannya. Sebenarnya ada banyak teori uji kebenaran dalam
epistemologi. Penulis hanya mengambi tiga dari teori-teori uji kebenaran tersebut
yaitu; teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan otoritarianisme;
1. Teori kebenaran korespondensi adalah persesuaian antara apa yang
dikatakan dengan kenyataan atau realita. Suatu proposisi dikatakan
benar apabila proposisi itu saling bersesuaian dengan dunia kenyataan
yang diungkapkan dalam pernyataan itu, atau fakta yang menjadi objek
pengetahuan.108 Dalam konteks hukum, suatu hukum dikatakan benar
atau mempunyai validitas, ketika dia mempunyai korespondensi dengan
kenyataan atau realitas yang hidup yang dihadapi oleh masyarakat.
Hukum yang tidak punya relevansi dengan kondisi riil masyarakat pada
hakikatnya bukanlah hukum. Salah satu tokoh yang menggunakan ini
adalah Imam al-Syatibi.
2. Teori kebenaran koherensi adalah sesuatu dianggap benar ketika dia
mempunyai kesesuaian (koheren) atau keharmonisan dengan sesuatu
yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.109 Hierarki yang lebih tinggi
di sini adalah berupa teks-teks, baik itu al-Qur‟an maupun Hadis. Ahli
hukum yang menggunakan ini adalah Imam al-Ghazali.
3. Teori kebenaran otoritarianisme adalah teori yang membuktikan telah
ada danterjadinya perilaku otoritarian dan despotik oleh seseorang atas
orang lain, baik karena didasarkan atas otoritas koersif maupun
persuasif.110 Kebenaran dalam teori ini didasarkan pada pemegang
otoritas.
c. Aksiologi Hukum Islam
Secara sederhana aksiologi adalah theory of value, teori tentang nilai.
Objek kajian aksiologi adalah apa nilai guna dari ilmu pengetahuan. Dalam
konteks hukum, ia merupakan wilayah yang membicarakan kegunaan hukum dan
nilai-nilai.111
Dengan demikian, pertanyaan yang mendasar dalam aksiologi, untuk
apa hukum itu dibuat? Apa nilai guna yang terkandung dalam pelaksanaan
108
Shofiyullah Mz, Epistemologi Ushul Fikih al-Syafi‟i (Yogyakarta,Cakrawala Media, 2010), 34. 109
Noeng Muhadjir…, 18. 110
Khaled Abou El Fadl membedakan antara being in authority (memangku otoritas) dengan being
an authority (memegang otoritas). Being in authority melahirkan otoritas yang berisifat koersif,
dimana kepatuhan terhadap seseorang berdasar pada posisi struktural dalam suatu institusi resmi
yang dimilikinya. Sementara being in authority melahirkan otoritas persuasif, dimana kepatuhan
terhadap seseorang kerena memiliki keahlian khusus. Lihat Shofiyullah Mz, Epistemologi Ushul
Fikih Al-Syafi‟i... 38-48. 111
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia,
cet. ke-4 (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), 175.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
57
hukum? Seberapa jauh hukum itu memberikan kemaslahatan?, dan lain-lain.
Hukum Islam bertujuan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan
akhirat. Karena tujuan adanya hukum Islam itu sendiri merupakan manifestasi dari
sifat raḥmān dan raḥīm (Maha Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada
makhluk-Nya. Dan inti dari hukum Islam atau syariah adalah raḥmatan lil
‘ālamīn.112
Mengapa kemudian akhirat menjadi yang notabenenya merupakan
sesuatu yang bersifat eskatologi ikut menjadi tujuan dari hukum Islam? Hal ini
bisa dijawab, bahwa hukum Islam (syariah dalam arti sempit) tidak hanya memuat
kaidah-kaidah hukum an sich semata, tetapi meliputi juga kaidah-kaidah
keagamaan, kesusilaan, dan sosial.113
Tidak seperti hukum barat, yang
orientasinya hanya kepada nilai-nilai formal dan nilai-nilai non-formal dari hukum
itu sendiri.
1). Objek Kajian Filsafat Hukum Islam ada 5, yaitu:
a. Tentang Pembuat Hukum Islam (al-Hakim) yakni Allah SWT. Yang telah
menjadikan para nabi dan Rasul terutama nabi terakhir Muhammad SAW
yang menerima risalah-Nya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di
dalam kitab suci al-Quran. Dan keberadaan Muhammad SAW yang
eksistensinya yang mungkin ada (mumkinah al-Maujudah);
b. Tentang sumber ajaran hukum Islam, berkaitan dengan kalamullah yang
tertulis atau quraniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya cipta-
Nya atau ayat-ayat Kauniyah.
c. Tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam Ilahi yakni
orang Mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan
untuk memilih;
d. Tentang tujuan Hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf
dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah;
112
Fathurrrahman Djamil…, 15. 113
Hukum barat hanya berisi kaidah-kaidah hukum an-sich semata, yang didukung oleh sanksi
yang dapat ditegakkan secara paksa. Sementara hukum Islam selain berisi kaidah hukum juga
bisa berisi: kaidah agama, kesusilaan, dan sosial. Lihat Syamsul Anwar, Legal Drafting
Terhadap Materi Islam: Perspektif Hukum Islam, dalam Syamsul Anwar dkk, Ontologi
pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas (Yogyakarta, Fak. Syariah
dan Hukum, UIN Suka, 2008), 214.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
58
e. Tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-
dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits serta
pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalan.
Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia
dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan
manifestasi dari sifat rahman dan rahim (maha pengasih dan maha penyayang)
allah kepada semua makhluk-nya. Rahmatan lil-alamin adalah inti syariah atau
hukum Islam. Dengan adanya syari‟ah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di
muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada
semua orang.114
2. Prinsip-Prinsip Dasar Filsafat Hukum Islam
Untuk memahami, mengetahui, dan menggali filsafat hukum Islam115
diperlukan sebuah kerangka metodologi. Artinya, metodologi digunakan sebagai
rentetan dalam membangun suatu tatanan teori dalam hukum Islam bahkan
sampai membangun tatanan peraturan dalam pemikiran. Dalam hal ini,
metodologi yang digunakan ialah falsafah al-tasyri>‟ dan falsafah al-syari>’ah yang
dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum
(h}ikmah al-tasyri>‟) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (asra>r al-
ah}ka>m). Dua hal ini juga yang menjadi kerangka dasar dan platform dari
konstruksi hukum Islam.
Para ahli Ushul Fiqih, sebagaimana ahli Filsafat Hukum Islam, membagi
Filsafat Hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu: Pertama, Falsafah al-tasyri>’
114
Juhaya S. Praja…, 15. 115
Lebih detailnya lihat dalam Syaiful Annas, Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd dan Implikasinya
terhadap Hukum Keluarga: Studi Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (karya
ilmiah tidak diterbitkan) (Yogyakarta: Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga, 2008).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
59
(Objek Teoritis) adalah filsafat yang memancarkan, menguatkan, dan memelihara
hukum Islam atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan
hukum Islam.116
Kedua, Falsafah al-syari>’ah (Objek Praktis) adalah filsafat yang
diungkapkan dari materi hukum Islam, seperi ibadah, mu‘a>malah, jina>yah,
‘uqu>bah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia,
kelebihan kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan
dengan hukum yang lain.117
Falsafah tasyri>’ (Objek Teoritis) selanjutnya akan kita uraikan tentang
pembagiannya sebagai berikut:
a. Da>im ‘al-ahka>m (dasar-dasar hukum Islam);
b. Maba>di >’ al-ahka>m (prinsip-prinsip hukum Islam)‟
c. Us}u>l al-ahka>m (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir
al ahkam (sumber-sumber hukum Islam);
d. Maqa>s}id al-ahka>m (tujuan-tujuan hukum Islam);
e. Qawai>d al-ahka>m (kaidah-kaidah Hukum Islam).
Pertama, da’a>im ‘al-ah}ka>m al-Isla>m (dasar-dasar hukum Islam). Asas-
asas pembinaan hukum Islam yang dikatakan da’a>im al-tasyri>’ atau‘al-h}ukm
antara lain adalah:
a. Menghilangkan kesulitan (nafyu al-h}araj); b. Menyedikitkan beban (qillah al-takli>f); c. Membina hukum dengan menempuh jalan tadarruj (gradual). Artinya,
hukum tidak dilimpahkan sekaligus, akan tetapi satu demi satu atau tahap
demi tahap yang nantinya tidak “merasa berat” untuk melaksanakannya;
d. Seiring dengan kemaslahatan manusia. Pembinaan hukum memerhatikan
kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan
mereka serta iklim yang menyelubunginya;
e. Syara yang menjadi sifat za>tiyyah Islam.
116
Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press, 2007), 11. Lihat juga
dalam Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 117
Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam…, 12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
60
Dengan kerangka ini, kebanyakan hukumnya diturunkan secara mujmal
sehingga memberi lapangan luas kepada para mujtahid untuk berijtihad dan di sisi
lain memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya
hukum Islam itu menjadi elastis sesuai dengan tabiat perkembangan manusia yang
berangsur-angsur.
Kedua, maba>di’ al-ah}ka>m al-Isla>m (prinsip-prinsip hukum Islam). Titik
tolak atau prinsip-prinsip hukum Islam ialah:
a. Prinsip tauhid;
b. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah;
c. Prinsip menghadapkan khita>b kepada akal;
d. Prinsip memagari akidah dengan akhlak (moral) yang utama sehingga
dapat mensucikan jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang;
e. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi untuk kebaikan jiwa
dan kesuciannya;
f. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum;
g. Prinsip persamaan. Hukum Islam menyamaratakan manusia dan tidak ada
perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, antara individu
dengan individu yang lain;
h. Prinsip menyerahkan masalah ta’zi>r kepada pertimbangan penguasa atau
para hakim;
i. Prinsip tah}ki>m. Masalah tah}ki>m hanya dapat diperbolehkan dalam
masalah-masalah kehartaan;
j. Prinsip menyuruh ma‘ru>f dan mencegah munkar;
k. Prinsip toleransi (tasammuh);
l. Prinsip kemerdekaan; dan
m. Prinsip hidup bergotong-royong, jamin-menjamin kehidupan bersama,
bantu membantu antar sesama anggota masyarakat.
Ketiga, us}u>l al-ah}ka>m al-Isla>m (sumber-sumber hukum Islam atau pokok-
pokok hukum Islam) atau mas}a>dir al-ah}ka>m (sumber-sumber Hukum Islam).
Mengenai us}u>l al-ah}ka>m atau mas}a>dir al-ah}ka>m al-Isla>mi yang paling utama
adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah yang tidak diragukan lagi ke-qat}’i-annya. Lalu
berkembang beberapa metode istinba>t} hukum Islam yang dijadikan pegangan
dalam menentukan sebuah hukum, meskipun beberapa metode hukum tersebut
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
61
masih dipertentangkan ulama, di antaranya ialah ijma>’, qiya>s, istih}sa>n, mas}lah}ah}
mursalah, istis}h}a>b,‘urf, saddud zari>’ah, syar‘u man qablana>, dan lain sebagainya.
Keempat, qawa>‘id ‘al-ah}ka>m al-Isla>m (kaidah-kaidah hukum Islam). Ini
adalah berupa kaidah-kaidah istinba>t} yaitu‟ amr, nahyu, „a>mm, kha>s}, mut}la>q,
muqayyad, mujmal, dan mufassar atau segala kaidah yang berhubungan dengan
kebahasaan, yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, uslub-uslub dan tarkib-
tarkib-nya. Kemudian kaidah fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah kulliyyah yang digali
dari nas-}nas} al-Qur‟an, al-Hadis dan dari ru>h}al-syari’ah (jiwa syariat).118
Sedangkan kelima, maqa>s}id al-ah}ka>m al-Isla>m yang merupakan tujuan-tujuan
hukum yang karena tujuan-tujuan tersebut hukum disyariatkan dan diharuskan
bagi para mukallaf untuk menaatinya.
Falsafah al-syari>’ah (Objek Praktis) adalah filsafat yang diungkapkan
dari materi hukum Islam, seperi ibadah, mu‘a>malah,jina>yah, ‘uqu>bah, dan
sebagainya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia, kelebihan
kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan
hukum yang lain.119
Menurut Hasbie as-Shiddiqie kajian yang komprehensif
dalam pembagian Falsafat Syari‟ah dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:
a. Asra>r al-ahka>m (rahasia-rahasia hukum Islam);
b. Khasa>is al-ahka>m (cirri-ciri khas hukum islam);
c. Maha>sin al-ahka>m atau maza>ya> al-ahka>m (keutamaan- keutamaan
hukum Islam);
d. T}awa>bi’ al-ahka>m (karateristik hukum Islam).
Pertama, asra>r al-ah}ka>m al-Isla>mi (rahasia-rahasia hukum). Filsafat ini
merupakan bagian urgen dan patut diberikan perhatian, karena dengan filsafat ini
118
Hasbi Ash Shidieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 40-41. 119
Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam…, 12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
62
kita akan mampu menanggapi rahasia/sirr dari perintah-perintah syara‟ dan
larangan-larangannya. Untuk memperdalam hal ini, perlu dilakukan kajian seperti:
a. Ah}daf al-ah}ka>m (tujuan-tujuan akhir Islam) yang merupakan salah satu
cara untuk memahami asra>r al-ah}ka>m. Dalam hal ini, terdapat dua jalan
yang perlu dipahami, yaitu‟illat hukum dan hikmah hukum. Untuk
memahami ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum
itu mempunyai „illat atau tidak, atau apakah hukum itu semuanya ma‘qu>l al-ma‘na atau ghairu ma‘qu>l al-ma‘na; dan;
b. Pandangan ulama dalam mengungkap rahasia hukum.
Kedua, khas}a>is} al-ah}ka>m al-Isla>mi (karakteristik hukum Islam) yang
terdiri dari:
a. Rabba>niyyah (ketuhanan), artinya Allah yang mengatur perjalanan hidup
dan kehidupan manusia agar dapat membina hubungan antar individu
maupun jamaah di atas landasan yang kokoh, jauh dari kekerdilan,
ekstremitas, hawa nafsu, dan pertentangan manusia;
b. insa>niyyah (kemanusiaan), Ciri kemanusiaan (humanisme) dalam
pandangan Islam tidak bertentangan dengan ciri rabba>niyyah, karena
takdir manusia memiliki kedudukan dalam pencapaian tujuan-tujuan Islam
yang begitu tinggi, yakni keberuntungan dan kebahagiaan manusia;
c. Syumu>l. Ke-syumul-an Islam, termasuk di dalamnya syari‟at (hukum),
berlaku di segala zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia;
d. Waqi>’iyyah (realistis); Artinya, tidak mengabaikan konteks atau realitas
yang terjadi, yang ada pada setiap sesuatu yang dihalalkan atau
diharamkan; dan
e. Tana>suk (keteraturan), yakni bekerjanya semua individu dengan teratur
dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, dengan tidak saling
benci dan menghancurkan.
Ketiga, mah}a>sin al-ah}ka>m al-Isla>mi (keutamaan hukum Islam). Pada
tataran ini, hukum Islam yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat, memiliki
mah}a>sin atau keistimewaan-keistimewaan yang apabila diterapkan dalam
kehidupan masyarakat secara bersama-sama akan membentuk masyarakat yang
ideal, yakni masyarakat adil, kesetaraan, kebebasan, dan sebagainya.
Keempat, tabiat dan watak hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak
(tabiat) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Watak
atau tabiat dan ciri khas tersebut adalah:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
63
a. Taka>mul, artinya sempurna bentuknya dan tuntas;
b. Wasat}iyyah, yang berarti imbang harmonis, ifra>t dan tafri>t; dan
c. H{arakah, yang berarti bergerak dan berkembang, serta ber-tat}awwur
sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Konsep Filsafat Hukum Islam
Salah satu langkah yang mendasari pemikiran maqashid syari'ah sebagai
instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah ditetapkannya hukum Islam.
Maqa>s}id syari >’ah penting untuk dipelajari dan difahami, karena dengannya
wawasan kita tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak akan
mampu untuk menemukan hukum dalam menetapkan hukum Islam, sebelum ia
memahami secara benar, maksud dan tujuan Allah mengeluarkan perintah dan
larangan-Nya. Maqa>s}id syari>’ah adalah: tujuan yang menjadi target nash dan
hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik
berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan
umat.120
Tujuan hukum menurut al-Juwaini> ada tiga macam, yaitu primer,
sekunder, dan tersier. Pemikiran al-Juwaini> tersebut dikembangkan oleh muridnya
yakni al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud hukum dalam kaitannya
dengan pembahasan tema maslahat. Maslahat menurut al-Ghazali adalah
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam maslahat di
120
Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan hukum dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu; Meneliti
setiap illat nash Al-Quran dan As-Sunnah. Meneliti, mengikuti, dan memikirkan hukum-hukum
partikular. Untuk kemudian menyatukan antara satu hukum dengan hukum yang lain, agar dari
penelitian ini kita dapat menemukan tujuan hukum yang menjadi maksud Allah dalam membuat
hukum-hukum tersebut. Lihat Yusuf Qardhawi…, 18.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
64
atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika
dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder, dan tersier.121
Tujuan hukum bisa juga disebut dengan hikmah-hikmah dibalik hukum itu
sendiri. Karena dalam setiap hukum yang disyari‟atkan oleh Allah untuk
hambaNya pasti terdapat hikmah. Ada perbedaan pemahaman hikmah dan illat
hukum (motif penetapan hukum) yang disebutkan oleh para ahli ushul fikih dalam
bab qiyas dan didefinisikan dengan‚sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan
hukum. ‛Illat sesuai dengan hukum, tetapi ia bukan tujuan dari hukum itu.122
„Illat
rukhsah ketika dalam perjalanan jauh baik dalam bentukjama‟-qashar atau
berbuka puasa pada bulan Ramadhan adalah perjalanan itu sendiri (safar), sedang
hikmah rukhsah karena adanya kesusahan yang dirasakan sewaktu dalam
perjelanan itu. Para ahli ushul fikih tidak menyatukan antara illat hukum dan
hikmah kerana hikmah sulit untuk ditetapkan. Contohnya; jika kesusahan itu i‟llat,
mungkin ada orang yang mengatakan saya tidak susah.
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu
mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari
keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan
Hukum Islam.123
Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan
bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan
121
Muhammad Hashim Kamali, Shari‟ah Law: An Introduction, (Oxford: Oneworld Publications,
2008), 127. 122
Yusuf Qardhawi…, 18. 123
Ibn Qayyim, I‟la>m al-Muwaqi’i>n Rabb al-„’A>lami>n, (Beirut: Da>r al-Jayl, t.th.), Jilid III, 3.
lihat juga Izzuddi>n Ibn Abd al-sala>m, Qawa>id al-Ahka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m, (Bairut: Dar al-
Jail, t.thn), jilid II, 72. Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),
Jilid II, 1017.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
65
hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang
tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif ma la yutaq‟ (membebankan
sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).124
Dalam rangka mewujudkan
kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh
merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini
wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.
Kelima misi (Maqa>s}id al-Syari >’ah/Maqa>s}id al-Khamsah) dimaksud adalah
memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.125
Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi
membagi kepada tiga tingkat, dharu>riya>t, hajiya>t dan tahsi>ni>ya>t. Pengelompokan
ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara
hirarkhis akan terlihat kepentingan dan siknifikansinya, manakala masing-masing
level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharu>riya>t
adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila
kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas.
Sementara level hajiyya>t tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan
bagi manusia. Selanjutnya pada level tahsi>niyya>t, adalah kebutuhan yang
menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan
Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek dharu>riya>t
nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek dharu>riya>t, keharusan
menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyyat, dan menutup aurat merupakan 124
Al- Syatiby, al-Muwa>faqa>t fi Usu>l al-Syari>’ah,‘(Kairo: Mu}stafa> Muhammad, t.th.), 150. lebih
lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam Fathi al-daraini, al-manahij al-Usuliyyah fi Ijtihadbi al-Ra‟yi fi al-Tasyri‟, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28; Muhammad
Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), 366; Muhammad Khalid
Mas‟ud,‘Islamic Legal Philosophiy, (Islamabad; Islamic Research institute, 1977), 223. 125
Ima>m Abi> Ha>mi>d Muhammad bin Muhammad al-Ghaza>li>, al-Mustasfa> min „Ilm al-Us>}u>l, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 20.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
66
aspeks tahsiniyyat.126
Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk
memelihara kelima misi hukum Islam.
Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus
membahas maqa>s}id syari'ah adalah Izzuddi>n ibn abd al-Sala>m dari kalangan
Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat
secara hakiki dalam bentuk menolak keburukan dan menarik manfaat.
Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan
skala prioritas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lebih jauh lagi ia menjelaskan,
bahwa hukum harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia
maupun di akhirat.127
Pembahasan maqa>s}id syari>'ah dilakukan al-Sya>tibi> secara khusus,
sistematis, dan jelas. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah
menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik
di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hukum harus mengarah pada dan
merealisasikan terwujudnya kemaslahatan. Doktrin maqa>s}id syari’ >ah adalah satu,
yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia
maupun diakhirat. Oleh karena itu al-Sya>tibi> meletakkan posisi maslahat sebagai
illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.128
Pemikiran maslahat al-
Sya>tibi> ini tidak seberani gagasan at-Tu>fi>. Pandangan at-Tu>fi> mewakili
pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. at-Tu>fi> berpendapat bahwa
126
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari‟ah menurut al-Syatibi, (Jakarta: Logos wacana
Ilmu, 1997), 72. 127
Yusuf Qardhawi…, 136. 128
Al-Syathibi menyebutkan ada tiga (3) syarat yang diperlukan untuk memahami maqashid
Syari‟ah. Ketiga syarat itu adalah: 1. Memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab: lafaz „am,
lafaz Khas,musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz, dan nasakh. 2. Memiliki pengetahuan
tentang Sunnah. 3. Mengetahui sebab-sebab turunnya Ayat. Lihat Al-Syatibiy, 2-3.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
67
prinsip maslahat dapat membatasi Quran, Sunnah dan konsensus jika penerapan
teks Qur‟an, Sunah dan konsensus itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi,
ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tu>fi> tersebut adalah hubungan
antar sesama manusia.129
Dalam menempatkan Illat sebagai maslahah an-Nabha>ni> berbeda dengan
al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-
ulang, bahwa maslahat itu bukanlah „illat atau motif (al-ba>‘its) penetapan syariat,
melainkan hikmah, hasil (nati>jah), tujuan (gha>yah), atau akibat („aqi>bah) dari
penerapan syariat.130
Mengapa an-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan
„illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya
(shighat) tidaklah menunjukkan adanya „illat (al-‘illiyah), namun hanya
menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat.
Misalnya firman Allah Swt dalam al-qur‟an Surat al-Isra (17) ayat 82 dan al-
Anbiya ayat 107 yang berbunyi:
يوم م ال ع ل ل رحة لم إ اك ن ل رس اأ
Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam”. (QS: al-Anbiya‟: 107)
Menurut an-Nabha>ni>, ayat ini tidak mengandung shighat ta„lil (bentuk kata
yang menunjukkan „illat), misalnya dengan adanya lam ta‟lil. Jadi maksud ayat
ini, bahwa hasil (nati>jah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat
129
Muhammad Hashim Kamali…, 136-141. 130
Taqiyuddi>n an-Nabha>ni>, Asy-Syakhshiyah al-Isla>miyyah. Us}u>l al-Fiqh. (Al-Quds: Min
Mansyura>t Hizb at-Tahri>r. 1953), Juz, III, 359-360.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
68
bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil
pelaksanaan syariat, bukan „illat dari penetapan syariat.
Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Sai>d
Ramadha>n al-Bu>t}i> ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu;
1. Memperiotaskan tujuan-tujuan Syara‟;
2. Tidak bertentangan dengan al Qur‟an;
3. Tidak bertentangan dengan al Sunnah;
4. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas merupakan salah
satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan
kemashlahatan bagi mukallaf;
5. Memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar.131
Kemudian bagaimana penerapan teori maqa>s}id Shari >’ah ini dalam
menemukan nilai keadilan? Dalam kaitan dengan hal tersebut tentu teori maqa>s}id
Shari>’ah harus mampu menemukan fakta-fakta yang sebenarnya melalui analisis
filosofis terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Perumusan masalah dalam
proses penerapan hukum yang tepat dan benar perlu menjadi perhatian penting.
Menurut Taufik, mantan Hakim Agung/Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung
RI, apabila perumusan masalah dalam suatu perkara salah, maka proses
selanjutnya akan salah.132
Dalam merumuskan masalah yang perlu diperhatikan
adalah melakukan identifikasi terhadap masalah itu. Kemudian kategorisasi dalam
menentuan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, sehingga
nilai keadilan yang didealkan dapat tercapai.
Pada akhirnya, keadilan mengacu pada upaya hakim untuk menemukan
kebenaran dan memberikan hukum jika ada pelanggaran yang tidak ada aturan 131
Muhammad Sai>d Ramadha>n al-Bu>ti>, al-Dawa>bit al-Mashlahat fi al Syari>ah al-Isla>miyah,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977), 119-248. 132
Andi Syamsu Alam, Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding, dalam Majalah Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI), Tahun Ke XX No. 239 Agustus 2005), 41.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
69
tegasnya secara formal. Hal tersebut adalah bentuk dari keadilan prosedural.
Keadilan prosedural adalah aspek ekternal hukum, tempat keadilan substantif
direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif
hanya akan menjadi teori-teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat.
Meskipun demikian, selain keadilan, nilai kepastian dan kemanfaatan hukum juga
penting untuk dipertimbangkan dalam penegakkan hukum.133
B. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam
1. Pengertian Keadilan
Keadilan adalah salah satu kata yang memang susah untuk didefinisikan
secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya
secara nyata. Sama halnya dengan definisi hukum; sampai sekarang belum ada
orang yang mampu memberikan definisi yang lengkap dan memuaskan bagi
semua pihak. Walaupun definisi yang dikemukakan oleh seseorang dianggap
benar, tetapi orang lain dapat mengemukakan definisi lain yang juga dianggap
benar dan begitulah seterusnya. Masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi
bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan,
politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Namun apabila timbul pertanyaan
tetang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran apa yang digunakan untuk
menentukan sesuatu itu adil atau tidak.
133
Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat
nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar
hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang
lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan
adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungs verhaltnis). Theo Huijbers, Filsafat
Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 161.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
70
a. Definisi Keadilan
Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan
sesuatu (hukum) dengan benar.134
Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan
atau perlakukan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan
yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi
konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah
tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya. yang adil, meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1) Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya;
2) Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah;
3) Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan;
4) Berpihak atau berpegang kepada kebenaran;
5) Tidak sewenang-wenang.135
Keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya
sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai
dengan kadar/ketentuan masing-masing haknya.136
Keadilan merupakan salah satu
tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat
hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum
dan kemanfaatan. Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi
134
Abi> al-Fadhl Jamaluddi>n Muhammad ibn Mukarram ibn Manzu>r al-Afriqi> al-Mis}ri>, (Lisa>n al-‘Arab, Jilid XI, Beiru>t: Da>r Sader), t.t.,.
135 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern
English Press, 1991), 12. 136
Itulah yang dimaksud oleh firman Allah: “...dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”, An-Nisa ayat (58). Lihat Sayid
Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, (Terj. Haryono S. Yusuf), (Jakarta: Intermasa.
1981).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
71
kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan
hukum seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar
hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran
tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus
memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan
umat manusia.
b. Keadilan dan Moralitas
Dalam al-Qur‟an perintah berlaku adil dikaitkan dengan taqwa
(ketakwaan). Berlaku adillah kamu! Itu lebih dekat kepada taqwa (Q.S. al-
Maidah: 8). Dalam ayat ini orang-orang Mukmin bahkan diingatkan untuk tetap
teguh menegakkan keadilan dan mereka sama sekali tidak boleh berbuat curang
meski terhadap orang-orang yang mereka benci. Dalam ayat yang lain dikatakan
bahwa keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri atau keluarga
dekat sekalipun. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‟an surat an-
Nisa‟: 135 dan al-An‟am: 152 yang berbunyi :
ى ل ع و ول لمه ل اء د ه ش ط س ق ال ب ي ومام ق وا ون ك وا ن آم ين لمذ ا ا ي ه أ ا ي و أ م ك س ف ن أي رب والق ن ي د ل وا ل ا
Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah
membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena
ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis
yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling
dalam.137
Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa
yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak
137
Angkasa, Filsafat Hukum, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
72
dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil‚ neraca hukum yakni‚ takaran hak
dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya
merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan
kesebandingan hukum.138
Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya
berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:
a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan
besar kecil kewajibannya;
b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat
memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak
pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras
dengan haknya;
c. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan
kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian
pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya
tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya;
upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan
pekerjaannya.139
Dalam buku Philosophy of Islamic Law and Orientalists, Muslehuddin
menyitir pandangan Plato: "In his view, justice consists in a harmonious relation,
between thevarious parts of the social organism. Every citizen must do his duty in
his appointed place and do the thing for which his nature is best suited". Plato
dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang
memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme
sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan
sifat alamiahnya.140
138
A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2005), 176. 139
Ibid., 177. 140
Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, (Delhi: Markaz
Maktabah Islamiyah, 1985), 42.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
73
Hegel menyatakan dalam Philosophy of Rightnya, bahwa keadilan
memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya, keadilan
dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu
sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari
kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada
tataran sosial.141
Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, Habermas
mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi
individu. Dari perspektif modernitas, menjadikan hak serta penghormatan yang
sama bagi individu sebagai postulat merupakan realisasi kebebasan subjektif dan
individualitas yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Sedangkan tentang
solidaritas, Habermas berpendapat bahwa‚solidaritas mempostulatkan empati dan
perhatian bagi keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat. Dengan kata lain,
solidaritas mengacu pada keberlangsungan ikatan anggota komunitas yang secara
intersubjektif menempati dunia kehidupan yang sama.142
Pandangan hegel diperkuat Habermas, bahwa keadilan dan solidaritas
adalah dua muka dari keping uang logam kehidupan sosial yang sama. Karena,
etika diskursus praksis komunikatif deliberatif diskursif, dan menawarkan
prosedur yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mempengaruhi
hasil konsensus dengan kesetujuan, maupun dengan ketidaksetujuan di satu sisi.
141
Hegel menyatakan bahwa; moralitas berfungsi untuk melindungi kebebasan di tataran subjektif,
maupun kebebasan di tataran sosial. Kebebasan subjektif, jika disintesakan dengan piranti
filosofis ala Kant, mempostulatkan rasa hormat dan hak yang sama. Sementara kebebasan di
tataran sosial mempostulatkan empati dan perhatian terhadap masyarakat sekitar dimana individu
itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain, yang pertama mempostulatkan keadilan, yang
kedua mempostulatkan solidaritas. Keadilan dan solidaritas adalah elemen kehidupan sosial yang
tak terpisahkan. Lihat Bur Rasuanto, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan
Habermas, Dua Teori FilsafatPolitik Modern (Jakarta: Gramedia, tt), 150. 142
Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, (Cambridge: MIT Press,
1990), 200.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
74
Di sisi lain, diskursus komunikatif juga tidak merusak ikatan sosial yang
merupakan latar belakang para partisipan diskursus, yang juga menyadari
keanggotaannya didalam suatu komunitas komunikasi yang tak terbatas.143
Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti
keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang
apa yang menjadi haknya (fiatjutitia bereat mundus). Selanjutnya dia membagi
keadilan dibagimenjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah
keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat
jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip
kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang
menjamin,mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan
ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan
menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang
bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang144
atau
kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang
diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan
hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. Berdasarkan filsafat hukum
Aristoteles, inti dari filsafat hukum adalah hukum hanya bisa ditetapkan dalam
kaitannya dengan keadilan.145
143
Jürgen Habermas, Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics, (Oxfords:
Polity Press, 1990), 1-2. 144
Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum, (Surabaya:
LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010), 64. 145
Aristoteles mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu.
Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat
bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang
sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan
Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
75
2. Konsep Keadilan Dalam Islam
Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-
benarsepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang
lebih besar yang bekerja di balik scenario yang berkembang atas landasan spiritual
untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi
semua.Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia
tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.146
Dengan kata lain, adil
merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.
Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung.
Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh
hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita
luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya
negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan
perintah untuk menegakkan keadilan147
karena Islam menghendaki agar setiap
orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya,
keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya,
keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok
rethoric. LihatCarl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa
dan Nusamedia, 2004), 239. 146
Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam
Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith,
Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 151. 147
Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat
al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-
A‟raf ayat 96.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
76
yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-adl) di
dalam tatanan kehidupan masyarakat.148
Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau
istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Istilah lain dari al-„adl adalah al-
qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti
mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi
ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu
sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.149
Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi
keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan,
dan keadilan dalam hak-hak manusia.150
Terdapat beberapa istilah untuk
mengindikasikan kata al-adl.151 Beberapa sinonimnya adalah qisth,
152istiqa>mah,
wasath, nasib, hissa, mi>zan.153
Al-Adl berlawanan dengan jawar (ketidakadilan).
Terdapat beberapa sinonim jawar seperti zulm (kelaliman), tughya>n (tirani), dan
mayl (kecendrungan), inhira>f (penyimpangan). Secara bahasa, kata adl
diderivasidari kata „adala, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau
modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan
yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan;154
keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah adl sebagai
148
Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat, Jakarta:
Gema Insani Press, 2006), 249. 149
Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997), 25. 150
Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I,
268. 151
Ahmad Lutfi Fathullah, Al-Qur‟an Al-Hadi, dalam Tafsir Jalalain tentang Adil, dalam surat
An-Nisa‟ (4) ayat 58. 152
Moh. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu‟i…, 149. 153
Ibid. 154
Ibid., 74.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
77
kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu
dengan yang lain.
Makna kata adl bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna
yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di
hadapan hukum atau kepemilikian hak yang sama. Kalau dikatagorikan, ada
beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar
kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-
hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan Hendaknya kalian
menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.
Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur‟an surah al-Hujurat ayat 10 yang
berbunyi :
م ك وي خ أ ي واب ح ل ص أ ف وة خ إ ون ن ؤم م ل اا نم رحون إ ت م لمك ع ل وااللمه ت مق وا
Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan.
Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin
lebih tepat digunakan istilah nasib dan qisth (berbagi), qisthas dan mizan
(timbangan), dan taqwim (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan
kesahajaan mungkin terkandung dalam kata ta‟dil, qisth, dan washat. Kata ta‟dil
berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata
yang qisth dan washat secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan
tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat155
155
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih al-Bukhari…, 985.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
78
atau jalan tengah.156
Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak
memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-
wenang.157
Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua
setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara
individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan
masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara
serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.158
Keharusan berlaku adil pun harus dtegakkan dalam keluarga dan
masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam
diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa
membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria,
mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.159
Senada
dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya
perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.160
Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak
terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan
tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan
fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang
kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa
aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat
156
Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama, 289. 157
Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12. 158
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), 72. 159
Juhaya S. Praja…, 73. 160
Sayyid Qutb, Keadilan Sosial dalam Islam, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam
dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 224.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
79
material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuataan intelektual
semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan
manusia di Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang,
seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan
berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.161
Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam
al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri
menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi
juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam
pemerintahan.162
Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa
pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan
masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan
berlaku adil.163
Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:
a. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan
kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi
ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara
keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa
kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan.
b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada
kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru
dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan
jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan
kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.164
Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan,
mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari
161
Antony Black, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, diterjemahkan
dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present, (Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet. I, 208. 162
Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff…, 116. 163
Juhaya S. Praja…, 73. 164
Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), Cet. I, 34.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
80
keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang
hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam
bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat
haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.165
Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki
kedudukan tinggi dalam Islam.166
Kata adil” digunakan dalam empat hal, yaitu
keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang
berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi
berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya
sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.167
Keadilan
diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-
undangan (al-ada>lah al-qa>nu>niyyah), keadilan sosial (al-ada>lah al-ijtima>‟iyyah),
dan keadilan antar bangsa (al-ada>lah al-dauliyyah).168
Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan
oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara
benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah
ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.169
Apa pun sifatnya,
keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau
kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum
165
Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 214. 166
Pradana…, 49. 167
Murtadha Muthahhari, Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam, (Jakarta: Mizan
Pustaka, 2009), 65. 168
Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagaiAgama Universal,
(Yogyakarta: LKiS, 2004), 25-27. 169
Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Implementasinya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 46.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
81
dalam hidup bersama sebagai warga negara.170
Keadilan merupakan cita-cita
kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan
berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai
dengan posisi dan sifat alamiahnya.171
3. Bentuk-bentuk Keadilan Dalam Islam
a. Bentuk Keadilan
Keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan, namun
sangat sulit untuk menentukan batasannya. Ada beberapa bentuk keadilan
yang harus ditegakkan menurut Islam, secara garis besar dapat diungkapkan
sebagai berikut:
1) Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluq.
Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang
mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di
dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya
sesuai dengan Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan
yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya
dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal,
absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya
kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di
permukaan bumi ini.172
Alam ini diciptakan secara sempurna dan
170
Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2009), 42. 171
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2009), 47.
172
Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1989), 57.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
82
seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna
keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-
kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah
tangan manusia sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‟an surat
al-Rum ayat 41 yang berbunyi :173
ض ع ب م ه يق ذ ي ل النماس ي د ي أ ت ب س ك ا ب ر ح ب ل وا ر ب ل ا ف اد س ف ل ا ر ه ظ
ون ع رج ي م لمه ع وال ل م يع المذ
Dalam Islam, keadilan ilahi diabadikan dalam wahyu ilahi dan
kebijaksanaan Nabi yang disampaikan kepada umatnya. Wahyu, ditransmisikan
dalam firman Allah, yang ditemukan di dalam al-Qur'an, dan kebijaksanaan ilahi
itu diucapkan dengan kata-kata Nabi dan diumumkan sebagai sunnah. Ini dua
sumber tekstual yang tersedia sebagai bahan baku untuk hukum Islam dan
Keadilan.174
Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang keadilan sebagai berikut:
Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak
kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah
baik. Oleh karena itu, dituturkan, Allah menolong negara yang adil
walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim,
walaupun negara itu Mukmin.175
Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang bersifat syar‟i, yakni
istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam, yaitu al-Qur'an
dan al-Sunnah, baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan sanksi
ataupun hukum-hukum lain. Secara umum apa yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-
173
Lihat Sayid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, (Terj. Haryono S. Yusuf), (Jakarta:
Intermasa. 1981). 174
N. Hanif, Islamic Concept of Crime and Justice, (New Delhi: Sarup & Son, 1999), Cet. I,.
Pendahuluan. 175
Ibnu Taimiyah, Majmu‟ al-Fatawa, Juz VI, 322.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
83
Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, misalnya
makan harta yang bathil.176 Keadilan dan kebenaran atau kejujuran ini harus selalu
seiring sejalan dan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.177 Allah akan
menjunjung negara yang adil meskipun kafir dan tidak menjunjung negara yang tidak
adil sekalipun Muslim dan bahwa dunia akan dapat terus bertahan dengan keadilan
sekalipun kafir dan tidak akan bertahan dengan ketidakadilan sekalipun Islam.178
Penegakan keadilan ada yang cukup dengan petunjuk dari al-Qur'an dan neraca
keadilan (mizan), dan sebaliknya dengan kekuasaan (besi).
Imam al-Qurthubi memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang
diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam179
Allah SWT
memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan
keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara
tiba-tiba hari perhitungan (kiamat).180
Sedangkan al-Mawardi melihat sistem pajak
harus menerapkan keadilan baik kepada pembayar pajak maupun kepada bait al-
ma>l. Menuntut lebih dari adalah berlaku tidak adil terhadap hak rakyat,
sementarameminta lebih rendah juga tidak fair terhadap hak baitul mal.181
Keadilan komprehensip menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang,
ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan
176
Ibnu Taimiyah, al-Siya>sah al-Syariiyyah, (Beiru>t: Da>r al-Ma‟arif ‘li al-Thiba>’ah wa al-Nasyr,
t.t.), 15. 177
Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan
Harakah,(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 256. 178
Ibnu Taimiyah, al-Hisbah, (1967), hal. 94. Lihat juga Umer Chapra, Masa Depan Ilmu
Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 146. 179
al-Qurthu>bi>, al-Ja>mi‟ li Ahka>m al-Qur'a>n, (….), Juz X, hukum, 165. 180
al-Qurtu>bi>, al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qur’a>n, juz 17, 15. 181
Al-Mawardi>, al-Ahka>m al-Sult}a>niyyah, (1960), hal. 209.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
84
keturunan, dan kemanan kedaulatan, dan tidak ada unsur yang lebih cepat
menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.182
Mu‟tazilah mengusung keadilan, akal, kebebasan, dan kebijaksanaan atau
hikmah. Mutazilah dikenal dengan nama al-„Adliyyah. Wacana hikmah itu tidak
hanya merujuk pada prinsip keadilan Mu‟tazilah, tetapi juga merujuk pada prinsip
kebaikan dan keburukan rasional, kebebasan manusia, dan adanya tujuan-tujuan
tertentu dalam semua perbuatan ilahi.183
Mu‟tazilah percaya bahwa ada tindakan-
tindakan yang pada dasarnya adil dan ada tindakan-tindakan yang pada
hakikatnya tidak adil. Sebagai contoh, memberikan pahala untuk orang yang taat
dan menjatuhkan hukuman bagi pendosa merupakan suatu keadilan; dan Allah
Maha Adil, Dia memberikan pahala untuk orang yang taat dan menjatuhkan
hukuman bagi pendosa, dan mustahil Allah akan berbuat sebaliknya.
Keadilan Allah mengharuskan penciptaan manusia dengan diberi kuasa
dan kehendak selama ia terbebani kewajiban agama. Sehingga manusia mampu
menciptakan perbuatan-perbuatannya dan bertanggungjawab penuh atas
semuaperbuatannya, serta Allah tidak turut campur dalam segala tindakan
manusia.184
Mu‟tazilah cenderung memandang perbuatan Tuhan dari sudut
kepentingan dan kebaikan manusia, mereka mengatakan, bahwa masalah keadilan
erat hubungannya dengan hak. Keadilan diartikan memberi seseorang akan
haknya. Kata Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatan-Nya adalah
baik. Bahwa Ia tidak dapat berbuat buruk dan bahwa Ia tidak dapa mengabaikan
kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia. Selanjutnya, keadilan juga
182
Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), 57. 183
Murtadha Muthahhari, Keadilah Tuhan…, 23. 184
Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi‟i, diterjemahkan dari al-
Imam al-Syafi‟i „fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, (Jakarta: Hikmah, 2008), Cet. I, 114.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
85
mengandung arti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan
manusia dan memberi upah atau hukuman kepada manusia sejajar dengan corak
perbuatannya.185
Masalah keadilan186
ini dilihat dari sudut pandang manusia dan
mempunyai hubungan dengan hak dan kewajiban Tuhan. Bila al-„Adl
dihubungkan dengan hak berarti Tuhan bersifat baik, Tuhan tidak melupakan apa
yang wajib dikerjakan-Nya bagi manusia. Oleh karena itu Tuhan tidak bersifat
zhalim dalam memberikan hukuman, tidak meletakkan beban yang tak dapat
dipikul oleh manusia, dan memberikan upah kepada orang yang patuh pada-Nya,
serta memberi hukuman kepada orang yang menentang perintah-Nya.187
Bagi Ahlusunnah, sesuai dengan tendensi mereka untuk meninjau segala-
galanya dari sudut kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keadilan diartikan
dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yakni mempunyai
kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimilikinya serta mempergunakannya
sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan mengandung arti
bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya dan dapat
berbuat sekehendak hati-Nya dalam kerajaan-Nya. Ketidakadilan berarti
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yaitu berkuasa mutlak terhadap hak
milik orang lain. Keadilan. Tuhan khusus dimaksudkan bagi kebijaksanaan Tuhan
185
Tsuroya Kiswati, Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam, (Jakarta: Erlangga,
2007), 150. 186
Keadilan atau al-„Adil dalam teologi Mu‟tazilah mengandung dua makna. Pertama, keadilan
berarti perbuatan, maka setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh pelakunya agar dapat
dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan demikian, setiap perbuatan Allah dalam menciptakan
alam ini semuanya adil dalam arti perbuatan yang baik untuk dimanfaatkan. Kedua, keadilan
berarti pelaku perbuatan, berarti Allah tidak berbuat buruk atau jelek. Lihat Juhaya S. Praja,
Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), 75. 187
I. Nurol Aen, Relevansi Konsep al-Mushawwibat Dengan Dasar Teologi Mu‟tazilah (Studi
atas Pemikiran al-Qadhiy „Abd al-Jabbar), (Bandung: Gunung Djati Press, 1998), 54.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
86
menyiksa orang yang melanggar perintah-Nya.188
Asy‟ariyah menyatakan bahwa
Tuhan menciptakan perbuatan manusia dan manusia sendiri menjadi majbur
menghadapi persoalan yang rumit tentang keadilan.189
2) Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk
Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari
tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling
memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling
tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi
maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah
kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan
pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatannya atau kepentingan dan
kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan
dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri
sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman.
Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan sesama makhluk, maka
bentuk keadilan tersebut bisa termanivestasikan dalam kriteria sebagai berikut:
a. Keadilan dalam Pemerintahan; artinya berlaku adil dalam melaksanakan
kekuasaan menjamin kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum di
antara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan;
b. Keadilan dalam Peradilan. Seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak
boleh berat sebelah, dengan memberikan :
1) kesempatan yang sama untuk menemuinya;
2) perhatian yang sama
3) tempat yang sama;
4) penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.
188
Tsuroya Kiswati, Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam, (Jakarta: Erlangga,
2007), 151. 189
Ibnu Rusy, Tujuh Perdebatan Utama Dalam Teologi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2006), 57.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
87
c. Keadilan terhadap Semua Manusia. Berlaku adil terhadap semua orang
tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan
hitam, Arab dan „ajam, Muslim dan non Muslim serta berkuasa dan rakyat.
Al-Qur'an melembagakan zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin.
Nabi, ketika ia datang ke Madinah, melembagakan sistem persaudaraan dimana
penduduk lokal bersama semua yang mereka miliki berbagi dengan para
pendatang dengan memberikan rumah, kekayaan dan sebagainya. Islam memiliki
penekanan yang luar biasa pada keadilan sosial dan ekonomi.190
Konsep Islam
tentang kehidupan, alam semesta dan manusia yang tercipta secara harmonis.
Allah telah menciptakan alam semesta, Dia Maha Tahu tentang keadaan manusia
secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Allah memberikan kerangka Islam
dimana kehidupan dapat berkembang dengan damai dan harmonis dengan
keadilan dan kesetaraan.191
Pemikiran dalam Islam tentang keadilan dari aspek sosio-politik yang
menyatakan bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam
segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang
menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan
tenteram, meningkatkan etos kerja mereka, hingga meningkatkan dan
mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan.192
Harta dan pekerjaan akan memperkuat negara dan mempertahankan
kesinambungan pemerintahan, sebaliknya tindakan yang aniaya terhadap harta
manusia atau penghinaan terhadap hak kepemilikan akan mebuat rakyat malas
190
Nimat Hafez Barazangi and Friends, Islamic Identity and the Struggle for Justice, (Florida:
University Press of Florida, 1996), 16. 191
Sayed Khatab, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Teory of Jahiliyyah, (New York:
Routledge, 2006), 106. 192
Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam…, 269.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
88
bekerja dan selanjutnya timbullah malaise ekonomi,193
karena mereka terkena
krisis kepercayaan. Kemudian terjadilah krisis ekonomi yang akan
menghancurkan pembangunan dan melemahkan negara.194
Keadilan merupakan
landasan pembangunan peradaban dan prinsip awal agama.195
Keadilan adalah
tujuan manusia dalam seluruh kepemimpinan dan pemerintahan, dan mereka yang
memegang suatu kepemimpinan dan bagi setiap Muslim.196
Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk
menegakkannya, baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan
menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan
suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari
ektremitas dan ekses-ekses, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat
mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.197
Keadilan sebagai hal yang penting
bagi kaum Muslim, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan
sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang
bermacam-macam.198
Di tengah peningkatan wakaf uang di kalangan masyarakat,
hendaknya dana yang dikumpulkan bermanfaat untuk meningkatkan keadilan
193
Malaise ekonomi dapat diartikan kelesuan ekonomi. Periode kelesuan ekonomi dan
pengangguran secara besar-besaran pada tahun 1929 hingga masa sebelum perang dunia II. Lihat
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2010), 233. 194
Ibid., hal. 269. Al-Hurmuzan telah berkata kepada Umar ibn al-Khaththab ketika melihat Umar
tidur telentang di kebun, Kamu telah berlaku adil, merasa tenang, maka bisa tidur. Tidak ada
yang dapat cepat menghancurkan negara dan paling cepat merusak nurani rakyat kecuali
kelaliman. Karena tidak ada yang bisa mengatasinya dan memberhentikan tujuannya, semuanya
adalah kerusakan yang semakin lama semakin bertimbun menjadi besar. Sebagian hakim (bijak)
mengatakan, Keadilan adalah timbangan Allah yang telah diletakkan bagi makhluk-Nya dan
untuk mengukur kebenaran perbuatannya. 195
Ali Abdul Halim Mahmud, Fiqh Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim, 243. 196
Al-Nasa‟i meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah
SAW bersabda; Imam itu adalah perisai yang dipertahankan (dibela) ia di bekalangnya, dan
berlindungdengannya, maka jika ia memerintah dengan takwa dan adil, maka itu adalah pahala
baginya, dan jika ia memerintah bukan dengannya, maka ia mendapatkan dosanya. Lihat
Muslim binHajjaj, Shohih Muslim…, 1296. 197
Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi…, 59. 198
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
89
sosial.199
Konsep keadilan sosial dimaknai sebagai proses yang mengantarkan
masyarakat mencapai distribusi kekuasaan yang lebih setara dalam bidang politik,
ekonomi dan sosial.200
b. Azas-Azas Keadilan
Adapun azas-azas dalam menegakkan keadilan sebenarnya sangat banyak,
namun secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Kebebasan jiwa yang mutlak;
2. Persamaan manusia yang sempurna;
3. Jaminan sosial yang kuat.201
Dengan ketiga azas ini, jelas kelihatan bahwa manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal mempunyai kebebasan untuk memilih
sesuai dengan konsep dasar dan mempunyai posisi dan status yang sama dan akan
melahirkan suatu dinamika atau kekuatan yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar
yang sesuai dengan konsep Islam. Kebebasan jiwa adalah kebebasan untuk hidup
dan mengekspresikan diri secara sempurna sebagai manusia yang memiliki budi,
rasa dan karsa. Setiap manusia bebas berkreativitas secara positif, yakni sejauh
tidak merusak hak-hak dan kebebasan orang lain. Di sinilah keadilan menjadi
amanat bersama umat manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu.
Keadilan harus dilihat sebagai milik bersama dan atas dasar kebebasan yang
ditegakkan secara bersama-sama pula.
199
Azyumardi Azra, Dari Harvard Sampai Makkah, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), 18. 200
Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum
Modernis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 37. 201
Abu A‟la al-Maududi, Prinsip-Prinsip Islam, (Bandung: al-Ma‟arif. al-Mishriy, 1983), 141.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
90
Keadilan sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Allah SWT.
Karena itu, berbuat adil kepada apa pun dan siapa pun merupakan keharusan bagi
siapa saja dan kezaliman tidak boleh ditimpakan kepada apa pun dan siapa pun.202
Sebagian dari ajaran al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dengan menggunakan
kekuasaan. Oleh karena itu, penegasan ajaran agama bisa dilakukan dengan
mushaf dan kekuasaan.203
Tidak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi bahwa
Allah menyuruh berbuat adil atau Dia adalah Pelaku keadilan.204
c. Sarana Keadilan
Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup satu aspek kehidupan
manusia saja, tetapi semua aspek yang dibangun di atas tiang pokok yaitu hati
nurani yang ada dalam diri manusia (dhamir) dan pelaksanaan syari‟at secara
menyeluruh di lingkungan masyarakat. Kemudian Islam memadukan kekuatan
yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengalir dalam hati yang dimiliki
manusia.205
Sarana yang diperlukan dalam mewujudkan keadilan itu pada garis
besarnya terdiri dari dua aspek yaitu :
1) Syari‟at, sebagai kesatuan konsepsional atau gagasan teoritis.;
2) Manusia, dengan hati nurani dan sikap mental (persepsinya) yang benar-
benar siap untuk melaksanakan konsepsi yang tersebut di atas.
Keadilan bermakna kesamaan (equality), untuk memperoleh kebebasan
dan kesempatan.206
Keadilan hukum menyangkut keseluruhan hukum, sehingga
dapat dikatakan bahwa keadilan distributif dan keadilan komutatif terkandung
202
Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi…, 57. 203
Ibnu Taimiyah, al-Siya>sah al-Syariyyah fi Isha>h al-Ra‟yi wa al-Ra‟iyyah, (Mesir: Da>r al-Kita>b
al-Arabi>, 1979), 26. 204
Murtadha Muthahhari, Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam, (Jakarta: Mizan
Pustaka, 2009), 51. 205
Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1989), 200. 206
Ibid…, 46.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
91
dalam keadilan hukum. Di sinilah butuh keadilan seorang hakim meneliti berkas-
berkas yang masuk. Peganglah prinsip takwa dengan pakaian dan lidah yang
takwa, sebab hakim Muslim selalu dibantu oleh dua orang malaikat keadilan.207
Keadilan adalah bagian dari bukti ketakwaan tertinggi kepada Tuhan.208
Allah
menyuruh kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan khususnya keadilan
sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan
kaum fakir miskin.209
Sangat jelas Islam menaruh perhatian terhadap orang-orang
lemah (mustadh‟afiin) dan sebaliknya, kehancuran akan ditimpakan kepada kaum
muthrafiin, mereka yang kaya dan hidup bermewah-mewewahan.210
Keadilan
merupakan kemampuan menghormati semua orang tanpa memandang posisi
mereka dalam hidup atau relasi, memberikan setiap orang pelayanan yang
sama.211
Keadilan itu tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah, namun harus
terus diupayakan agar dapat terwujud.212
Tidak mungkin suatu negara dapat membangun tanpa keadilan.
Penindasan akan mengakhiri pembangunan dan keberakhiran pembangunan akan
dicerminkan dalam kelumpuhan dan kehancuran negara. Penindasan memiliki
konotasi yang lebih luas. Siapa pun yan merampas hak milik orang lain,
memaksanya bekerja berlawanan dengan kemauannya, mendakwa mereka secara
207
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet.
XVIII, 43. 208
Rasulullah SAW. bersabda: “Tiada seorang hakim dari kalangan hakim kaum Muslimin kecuali
selalu dibarengi dengan dua malaikat yang selalu membimbingnya ke arah masalah yangbenar
selama ia sendiri tidak menginginkan perkara selain yang benar itu. Bilamana ia sengaja
menghendaki perkara selain yang benar, maka kedua malaikat itu akan pergi darinya dan
menyerahkan dia ke hawa nafsunya sendiri”, (HR. Imam Thabrani melalui Imran r.a.). Lihat
Nasiruddin, Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam, (Jakarta: Penerbit Republika, t.t.), 6. 209
Mohammad Monib, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 198. 210
Ibid…, 200. 211
William J. Byron, The Power of Principles, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 122. 212
Maria S. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta:
Kompas Media Nusantara, 2001), 176.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
92
tidak benar, atau menimpakan beban pada mereka tanpa ada justifikasi dari
syariat, ia adalahseorang penindas.213
Pembangunan tidak dapat dicapai, kecuali
dengan keadilan, dan keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk
mengevaluasi manusia.214
Keadilan sebagai suatu isi pokok bagi semua aspek
kehidupan manusia dalam kerangka ajaran Islam.215
4. Keadilan dalam Pandangan Filosof Islam
Dalam perspektif Barat, hukum dan agama dipandang dua entitas yang
berbeda dan tidak ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya
berbeda ketika memahami hakikat hukum Islam. Negara dan hukum Islam
merupakan produk atau bagian (derivasi) dari Agama Islam itu sendiri. Ketiganya
adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai derivasi dari agama
Islam itu sendiri.216
Hukum Islam dipandang oleh para ahli sebagai hukum yang
berwatak ganda. Satu sisi dipandang abadi (tsawâbit ), sakral sebagai produk
Tuhan (wahyu).217
Namun, di sisi lain hukum Islam juga berwatak profan
(mutaghayyira>t) atau dinamis. Artinya, pada sisi lain hukum Islam juga
merupakan hasil kreasi manusia (ijtiha>d) dalam merespons dinamika kehidupan
manusia agar hukum Islam mampu menjawab perubahan.218
1). Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naiem Tentang Keadilan
213
Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi…, 58. 214
M. Suyanto, 11 Rahasia Memulai Bisnis Tanpa Uang, 128. 215
Sayyid Quthb, Al-„Ada>lah al-Ijtima>iyyah fi al-Isla>m, (1949). Lihat juga Umer Chapra, Masa
Depan Ilmu Ekonomi…, 59. 216
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1992), 38. 217
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, (Chicago: The University of
Chicago Press, 1969), 3. 218
Yu>suf al-Qaradha>wi>, al-Madkhal lî Dira>sah al-Syarî’ah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 22.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
93
Pembaharuan di dalam hukum Islam merupakan sebuah keniscayaan.
Gelora pembaharuan tersebut terus berjalan hingga kini. Salah satu pembaru
hukum Islam dari sarjana Muslim adalah Abdullah Ahmed An-Na‟im. Ia
menggagas pembaruannya dengan mengkritik teori dan praktik hukum Islam
tradisional (syariah historis). Khususnya masalah hukum perdata, hukum pidana,
hukum internasional, konstitusi Negara, hukum tata negara dan hak asasi
manusia.219
Pada dasarnya landasan berpijak dalam pemikiran An-Na‟im bertitik
tolak dari keharusan berlakunya hukum secara universal. Islam yang diagung-
agungkan sebagai agama universal, dalam kenyataannya tidak bisa diaplikasikan
secara universal.
Jika kelompok ulama perintis, seperti Umar bin Khattab melakukannya,
maka terbuka juga kesempatan bagi kaum Muslim kontemporer yang memiliki
kemampuan untuk melakukan formulasi ushul al-fiqh dan berhak melakukan
ijtihad sekalipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks al-Quran dan
Sunnah secara jelas dan rinci, sepanjang hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi
tujuan risalah Islam.220
Ini juga terlihat pada perdebatan antara Abû Hanîfah yang
rasionalis dengan metode istihsa>n-nya dengan Imam Syâfiî yang tekstualis dengan
qiyâs-nya. Pada masa modern dilanjutkan dengan Hasan al-Turabi yang
melakukan pembaruan terhadap us}u>l al-fiqh tradisional.221
Perdebatan antara akal
dan wahyu dalam hukum Islam terus berlangsung. Berangkat dari realitas di atas,
219
Abdullah Ahmed al-Na‟im, Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani
(pent.), (Yogyakarta: LKiS, 1997). 220
Ibid…, 56-57. 221
Hasan al-Turabi, Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis,
Abdul Haris dan ZaimulAm (pent.), (Bandung: Arasy, 2003), 51-73.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
94
maka An-Na‟im sebagai salah satu pembaru hukum Islam berkebangsaan Sudan
terpanggil untuk melakukan kritik secara internal dan eksternal.
Al-Na‟im telah berupaya melakukan pembaruan hukum Islam sejak di
Sudan. Tepatnya pada masa gurunya Mahmud Muhammad Tahâ. Al-Na‟im
terlibat langsung terhadap penyebaran ide dan gagasan pembaruan hukum Islam
yang diusung oleh Tahâ. Namun aktivitas ini terhenti ketika gurunya, Tahâ beserta
50 pengikutnya di penjara oleh rezim Ja‟far Numeiri. Termasuk al-Na‟im yang
turut dijebloskan selama 2,5 tahun. Mereka ditahan tanpa proses pengadilan
dengan dianggap melawan kebijakan pemerintah Numeiri yang memberlakukan
hukum Islam tradisional. Pada saat gurunya Tahâ dihukum mati pada rezim
Numeiri, akhir tahun 1984 al-Na‟im keluar dari Sudan. Hingga sekarang ia aktif
memberikan kuliah hukum Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia.
Metode Pembaruan al-Na’im
Kebutuhan mendesak yang dihadapi umat Islam dewasa ini, menurut al-
Na‟im, adalah memperbarui syariah historis. Al-Na‟im memahami syariah dalam
pengertian yang lebih luas. Menurutnya, syariah tidak hanya hukum Islam. Karena
syariah harus meliputi norma etik dan sosial, teori politik dan konstitusional, juga
aturan-aturan hukum mengenai hukum perdata dan hukum publik. Karena itu,
menurut al-Na‟im, syariah adalah formulasi historis dan sistem menyeluruh untuk
membedakan dari reformasi sebuah hukum modern yang mungkin dilakukan.222
Dalam memahami syariah, al-Na‟im menyatakan bahwa syariah pada dasarnya
222
Abdullah Ahmed al-Na‟im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and
International Law, (Syracuse:Syracuse University Press, 1990), 20, 31 dan 32. Lihat juga
Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan
Internasional dalam Islam, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (pent.), (Yogyakarta: LKiS,
1997), 27.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
95
merupakan hasil penafsiran yang berjalan, baik secara lambat, gradual maupun
spontan terhadap Alquran, dan juga hasil pengumpulan, verifikasi dan penafsiran
terhadap Sunnah selama tiga abad pertama.223
Al-Na‟im juga memasukan unsur-
unsur tafsir, ijtihad, fatwa ulama dan yurisprudensi sebagai bagian dari syariah.
Sebagaimana ungkapannya:
“Isi (pesan) Alquran dan Sunnah melahirkan dua level, yang pertama
merupakan periode awal Makkah, dan bagian berikutnya periode
Madinah. Pesan Makkah sebenarnya merupakan pesan abadi dan
fundamental dalam Islam, yang menekankan pemeliharaan martabat
seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, keyakinan
keagamaan dan lainnya”.224
Karenanya al-Na‟im menggugat sakralisasi hasil pemahaman syariah
historis, terlebih ia menilai syariah, sudah tidak lagi memadai dan tidak adil,
padahal syariah dipandang umat Islam merupakan bagian dari keimanan.225
Al-
Na‟im lebih berpijak pada pemikiran postmodernisme. Ia menolak segala bentuk
otoritas dan menegaskan akan relatifitas syariah. Syariah dipandang sebagai
produk pikiran manusia yang diproyeksikan dari al-Quran dan Sunnah. Karena itu
syariah tidak bisa lepas dari pengaruh ruang, waktu, konteks historis, sosial dan
politik penafsirannya. Dengan demikian, syariah menjadi tidak suci terlebih kekal
dan representatif untuk segala ruang dan waktu. Al-Na‟immengandaikan betapa
manusia mempunyai kewenangan bebas, kemampuan mengakses, memahami dan
bergumul dengan al-Quran dan Sunnah. Gagasan Al-Na‟imsejatinya tidak jauh
berbeda dengan para pemikir sekuler lainnya semisal Ashmawi, Nasr Hamîd,
Syahrûr, Arkoun dan sebagainya.
223
Muhammad Dahlan, EpistemologiHukum Islam al-Na‟im, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
86. 224
Abdullah Ahmed al-Na‟im…, 52. 225
Ibid…, xiv.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
96
Al-Na‟im juga menyadari bahwa tidak mungkin mayoritas umat Islam
secara terus menerus menerima sekularisasi dalam kehidupan publik mereka
karena kaum sekularis modern. Di mana elit yang memaksakan pembaruan
mereka melalui kontrol struktur kekuasaan. Akibatnya masyarakat muslim yang
akhirnya mengetahui prinsip-prinsip syariah hanya di permukaan saja. Dengan
demikian maka pendekatan yang lebih baik menurut Al-Na‟im dengan
mempertimbangkan hukum publik syariah dan pengalaman historis umat Islam
dengan standar yang berlaku pada waktu syariah diterapkan dan berusaha
mengembangkan prinsip-prinsip Islam alternatif bagi hukum publik untuk
penerapan modern.226
Pemberlakuan syariah historis untuk zaman modern ini
hanya akan membawa kepada kelemahan hukum Islam dalam pandangan dunia.
Sebaliknya, ketentuan syariah mesti dipahami sesuai dengan konteks modern.
Oleh karena itu penafsiran ulang, bahkan penafsiran total, ketentuan-ketentuan
syariah dalam al-Quran dan Sunnah merupakan sebuah keniscayaan.
b. Teori Nasakh Terbalik al-Na’im
Dalam melakukan hukum publik Islam, Al-Na‟imberangkat dan
menggunakan teori gurunya Mahmoud Mohammed Tahâ yang dikenal dengan
teori nasakh atau teori “nasakh terbalik”. Teori ini sejatinya merupakan bentuk
upaya rekonstruksi dari metode nasakh227
yang sudah mapan dalam kajian us}u>l al-
226
Ibid…, 44. 227
Bahwasanya dalam al-Quran ada ayat yang hukumnya muncul belakangan, maksudnya ayat
turunnya terlebih dahulu, kemudian hukum-hukum syariah dan fiqh yang terkandung di
dalamnya baru bisa diterapkan belakangan. Sehingga melahirkan metode nasakh. Termasuk
kesepakatan bahwa banyak ayat-ayat makkiyyah yang dihapus oleh ayat-ayat madâniyyah.
Terkait kategorisasi di atas, ada tiga pandangan ulama ushûl fiqh ketika mendiskusikan ayat-ayat
Makkiyyah dan Madâniyyah dengan pandangan sebagai berikut. Pertama, sebagian ulama
berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Hijrah, sedang ayat-ayat
Madâniyyah diturunkan sesudah Hijrah. Kedua, sebagian ulama berpandangan bahwa ayat-ayat
Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah, meski Nabi sudah hijrah. Ketiga,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
97
fiqh. Karenanya, perlu interpretasi yang memadai agar semangat yang
dikandungnya dapat ditangkap.228
Sejatinya kajian mengenai teori nasakh sudah
lama dilakukan dalam keilmuan us}u>l al-fiqh tradisional. Mayoritas ulama us}u>l al-
fiqh membagi kajian nasakh menjaditiga kategori:
a) Dihapus teksnya namun hukumnya tetap;
b) Dihapus baik teks maupun hukumnya; dan
c) Dihapus hukumnya namun teksnya tetap.229
Terkait dengan teorinya, al-Na‟im menyoroti pengertian yang ketiga,
yakni naskh al-h}ukm du>na tila>wah. Ketika menafsirkan ayat 106 Surat al-Baqarah
(2) yang berbunyi mâ nansakh min âyatin…, Al-Na‟immengikuti jejak gurunya
Tahâ, bahwa telah dihapuskan beberapa teks pra-Islam (risalah sebelum
Muhammad). Sedangkan kata-kata nunsihâ dimaknai dengan penundaan
pelaksanaan atau penerapan ayat tersebut. Selanjutnya, ungkapan na‟ti mitslihâ
aw bi khayrin minhâ ditafsirkan bahwa Allah akan mendatangkan ayat yang lebih
dekat kepada pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situasi mereka
ketimbang diartikan dengan makna ayat yang ditunda. Maksud utama dari “ayat
yang sepadan” adalah mengembalikan ayat yang sama ketika waktu
memungkinkan untuk menerapkannya. Dengan demikian, maka penghapusan
tersebut seakan-akan sesuai dengan kebutuhan situasi, dan ditunda sampai waktu
sebagian lagi ulama menentukan dari sisi isi dan tujuan ayat-ayat tersebut. Biasanya ayat-ayat
Makkiyyah diawali dengan redaksi “yâayyuha al-nas” sedangkan ayat-ayat Madâniyyah diawali
dengan yâ ayyuhal ladzîna âmanû. Lihat Manna al-Qathhan, Mabâhits fi „Ulum al-Qur‟an, (Ttp.:
Mansyûrat al-„Ashr al-Hadîts, t..t.), 56. 228
A. Luthfi Assyaukanie, Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer, dalam Jurnal
Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, No. 1, 1998. 229
Jalâluddin al-Suyûthi, al-Itqân fi Ulûm al-Qur‟ân, (Kairo: Dâr al-Turâts, 1967), 67-68.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
98
yang tepat bisa diterapkan hukum masing-masing, baik yang menjadi nâsikh
maupun mansûkh.230
Karena itu, metode yang ditempuh Al-Na‟im adalah, berdasar pada
bangunan periodesasi risalah yang dikenal periode Mekkah dan Madînah yang
harus dikaji ulang. Tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, suku dan ras,
keyakinan keagamaan dan lain sebagainya.231
Pesan-pesan Mekkah diindikasikan
dengan adanya penegasan persamaaan antara laki-laki dan perempuan dan
kebebasan penuh untuk menentukan keimanan dalam beragama.232
Menurut al-
Na‟im, sebagaimana dikutip Syaukani, ayat-ayat yang lahir pada periode Mekkah
mempunyai karakteristik yang dibutuhkan umat Islam saat ini. Metode
reaktualisasi ini melalui jalur na>sikh wamansu>kh yang dalam tradisi keilmuan
us}u>l al-fiqh diakui sebagai jalan tengahuntuk memisah ketegangan antara dua atau
lebih ayat yang seakan-akan kontradiktif. Dengan demikian, maka reaktualisasi
ayat-ayat periode Mekkah sebenarnya didasarkan pada kebutuhan kondisi dan
situasi yang tidak lagi relevan dengan periode Madînah. Karenanya, ayat-ayat
periode Madinah tersebut di-mansukh oleh ayat-ayat periode Mekkah.233
Metodologi ini kemudian disebut evolusi syariat yaitu; tafsir modern dan
evolusioner terhadap al-Qur‟an. Secara ringkas evolusi syariat bisa dijelaskan
sebagai berikut:
230
Abdullah Ahmed al-Na‟im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and
International Law, 58-60. Lihat juga Abdullah Ahmed al-Na‟im, Dekonstruksi Syariah: Wacana
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Ahmad Suaedy
dan Amiruddin Arrani (pent.), (Yogyakarta: LKiS, 1997). 231
Lihat Q.s. al-Baqarah [2]: 256, Q.s. Ali Imrân [3]: 64, Q.s. Yunus [10]: 99, dan al-Kahfi [18]:
29, tentang kebebasan beragama Q.s. al-Nisâ[ 4]: 1 dan al-Isrâ [17]: 70 tentang persamaan
martabat manusia tanpa menghiraukan agama atau jenis kelamin. 232
Abdullah Ahmed al-Na‟im…, 54. 233
Imam Syaukani, Rekontsruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya
Terhadap Pemabagunan Hukum Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), 142-44.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
99
a) Ia adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Quran dan as-
Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu
periode awal Mekkah dan berikutnya Madinah;
b) Pesan Makkah bersifat abadi, fundamental dan universal; sedang pesan
Madinah sebaliknya;
c) Syariat historis menjadikan ayat-ayat Madinah sebagai basis legislasi
syariat dengan menasakh (menunda pelaksanaan) ayat-ayat Mekkah yang
belum bisa diaplikasikan;
d) Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa diaplikasikan lagi karena
bertentangan dengan nilai-nilai modern;
e) Ayat-ayat Mekkah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi
syariat yang baru dengan menasakh ayat-ayat Madinah;
f) Di atas basis legislasi baru itu dibangun versi hukum publik Islam yang
sesuai dengan nilai-nilai modern yang tidak lain adalah pencapaian
masyarakat Barat saat ini.234
Dengan munculnya teori baru nasakh yang bangun oleh al-Na‟im, maka
hukum Islam akan lebih mudah untuk dikembangkan dalam konteks kekinian.
Sebab akan semakin jelas ayat-ayat mana saja yang akan digunakan dalam
konteks modern. Dari sini juga nampak bahwa sejatinya gagasan Al-Na‟imtetap
ingin mempunyai landasan yang otentik dalam melakukan pembaruannya, yakni
dengan tetap menjadikan Alquran sebagai korpus teks suci yang murni dan
tertutup. Dalam rangka upaya aktualisasi hukum Islam, Al-Na‟imberangkat dari
korpus tafsir (hasil kegiatan menafsirkan korpus pertama). Al-Na‟im tidak
mempertentangkan ayat-ayat yang ada, namun hanya mengkompromikannya
dengan konteks sosial.235
234
Mahmoud Mohamed Taha, Syariah Demokratik, judul asli, The Second Message of Islam,
terjemahan Nur Rachman, (Surabaya, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996), cet. 1, 179-
189. 235
Teori nasakh al-Na‟im mirip dengan pandangan al-Marâghi ketika menafsirkan Surat al-
Baqarah [2]: 106. Menurut al-Marâghi, bahwa hukum diundangkan untuk kepentingan manusia
dan kepentingan manusia dapat berbeda, karena perbedaan waktu, lingkungan dan situasi. Jika
suatu hukum diundangkan dan pada waktu itu dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu,
kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka merupakan tindakan bijaksana dengan langkah
menghapus hukum tersebut dan menggantikannya dengan hukum yang lebih relevan dengan
kebutuhan. Lihat Tafsîr al-Marâghi, Volume I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), 187. Bandingkan juga
dengan tafsirnya Rasyîd Ridhâ dengan pandangannya terkait nasakh dalam Alquran. Ia
mengatakan bahwa sejatinya hukum itu berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan situasi.
Apabila hukum yang diberlakukan pada saat itu karena sebuah kebutuhan, dan setelah kebutuhan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
100
Dengan teori ini, nampaknya Al-Na‟imjuga melihat akan pentingnya
kesesuaian antara ayat dengan konteks kultural masyarakat. Dalam bahasa al-
Sya>t}ibi> dalam maqa>s}id al-syari>’ah adalah menegakan kemaslahatan, yakni selain
melihat qashd al-sya>ri’ (tujuan Allah) juga harus mempertimbangkan qashd al-
mukallaf. Dengan bahasa yang lebih lugas,suatu perintah yang menjadi
pembebanan (taklîf) harus dipahami oleh semua subjeknya, baik secara
kebahasaan maupun kultural. Sehingga pembebanan tersebut senantiasa selaras
dengan kemampuan (qudrah) mukallaf, semisal mengurangi kesulitan
(masyaqqah) dan menarik kemaslahatan.236
Menurut al-Na‟im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan
fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah, bukan
madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Qur‟an
dan Sunnah periode Madinah, menurutnya, tidak merefleksikan pesan ayat-ayat
makkiyyah. Berdasarkan hal itu tentu saja konsep al-Na‟im ini perlu dikritisi. Di
antaranya konsep nasakh bagi ulama klasik adalah jalan terakhir ketika ayat-ayat
itu kelihatan bertentangan (ta‟arudh) dan tidak bisa dikompromikan dengan jalan
lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal menasakh ayat-ayat Makkiyyah dengan
ayat-ayat Madaniyyah. Apalagi model konsep nasakh-nya al-Na‟im yang
membalik proses nasakh, ayat yang turun lebih awal (makkiyyah) menasakh ayat
yang turun belakangan (madaniyyah). Ide-ide pembaruan yang dibawa oleh al-
Na‟im pada akhirnya berkesimpulan bahwa hukum Islam dalam segala
tersebut tidak dibutuhkan lagi, maka akan diganti dengan hukum yang lebih aplikatif dengan
kebutuhan waktu yang belakangan. Sayyid Rasyîd Ridhâ, Tafsîr al-Manâr, Volume I, (Bayrût:
Dâr al-Fikr, t.t.), 414. 236
Abu> Isha>q Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah, Jilid II, (Beiru>t: Da>r
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 20.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
101
dimensinya tidak dapat diubah hanya dalam bentuk reformasi hukum, tetapi harus
lebih jauh dari itu, yaitu dekonstruksi (merombak total) ketentuan syariah yang
sudah baku.
2. Filsafat Etika Mulla Shadra antara Paradigma Mistik dan Teologi
Persoalan etika atau moralitas selalu menarik untuk dikaji kapanpun atau
dalam kontek apapun. Tulisan ini membicarakan seorang filosof Muslim yang
memiliki kepedulian terhadap etika atau moralitas manusia, yaitu Mulla Shadra.
Filsafat moral yang ditawarkan oleh Mulla Shadra sering disebut dengan istilah
al-Hikmah al-Muta‟aliyah. Secara epistemologis al-Hikmah al-Muta‟aliyah
didasarkan pada tiga prinsip, yaitu pertama; intuisi intelektual (dzawaq atau
isyraaq), kedua; pembuktian rasional („aql atau istidlal), dan ketiga; syariat.
Dengan demikian, hikmah mengandung arti kebijaksanaan (wisdom) yang
diperoleh melalui pencerahan rohaniyah atau intuisi intelektual dan disajikan
dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan argumen-argumen rasional.
Hikmah ini bukan hanya memberikan pencerahan kognitif, tetapi juga realisasi
yang mengubah wujud penerima pencerahan itu merealisasikan pengetahuan
sehingga terjadi transformasi wujud hanya dapat dicapai dengan mengikuti
syariat.
3. Abu> Mans}u>r al-Matu>ridi>
Sebagai seorang teolog mumpuni, al-Maturidi memiliki pandangan
tersendiri mengenai keadilan Tuhan. Layaknya teolog Muslim kebanyakan, dia
meyakini Tuhan adalah Maha Bijaksana dan karenanya segala kehendak yang
menjadi pilihanNya tidak akan pernah berbenturan dengan prinsip-prinsip
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
102
fundamental keadilan. Pada saat yang sama, dia juga dikatakan sebagai teolog
Sunni pertama yang menyuarakan teori pengetahuan dalam teologi Islam di mana
dalam penyebutan sumber pengetahuan itu digunakan istilah sam (tradisi) dan „aql
(akal).237
Padahal jika dibaca secara seksama, konsepsi al-Maturidi tentang teologi
memiliki keunikan serta kharakteristik tersendiri, seperti ketika ia
mengartikulasikan pemikiran-pemikiran yang tentunya berkaitan dengan
persoalan utama ketuhanan (teologi).
Sebuah masalah yang mulanya dimunculkan kalangan Mu‟tazilah238
ketika
mempertanyakan status (kedudukan) pelaku dosa besar apakah tetap mukmin
ataukah telah kafir yang pada gilirannya melahirkan ragam faksi teologi (firqah)
di tubuh umat Islam. Sebagaimana Murji‟ah dan Asy‟ariyah, Qadariyah dan
Jabariyah, Maturidiyah turut andil dalam membincangkan masalah ini, termasuk
mengenai ada tidaknya hubungan antara perbuatan manusia dan kehendak mutlak
Tuhan. Sejalannya pandangan al-Maturidi dengan kalangan Mu‟tazilah dalam hal
perbuatan manusia atau bahkan lebih dekat dengan pendapat kelompok
Asy‟ariyah mengenai sifat-sifat Tuhan, menjadi semacam indikator penting
bagaimana al-Maturidi memiliki posisi tersendiri di wilayah pemikiran kalam.
Karenanya, menjadi wajar jika Harun menyebut bahwa al-Maturidi tidak
sepenuhnya bersifat Asy‟ariyah atau menjadi lawan bagi Mu‟tazilah, tetapi berada
pada posisi di antara keduanya (pertengahan).239
Dia tidak selalu condong kepada
Mu‟tazilah, juga tidak pula selamanya mengaminkan pandangan-pandangan
Asy‟ariyah.
237
Masturin, Khazanah Intelektual…, 23. 238
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur‟an: Semantics of the Qur‟anics Welthanschauung,
Kuala Lumpur: Islamic Book Trust. 2008. 239
Harun Nasution…, 34.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
103
Sekalipun pada gilirannya paham keagamaan ini (Maturidiyah) terbelah
menjadi dua haluan, yakni aliran Maturidiyah Bukhara dan Maturidiyah
Samarqand, hal itu tidak lantas menjadikan al-Maturidi sebagai pribadi memiliki
dualisme pandangan, terutama berkaitan dengan persoalan keadilan Tuhan.
Karenanya, menjadi penting untuk mengkonsepsikan pemikiran utuhnya
mengenai hal ini. Selain berupaya mendapatkan kemurnian pandangan dari al-
Maturidi sendiri, usaha yang demikian juga dalam rangka menempatkan al-
Maturidi pada posisi sejajar dengan al-Asy‟ari di ranah teologi. Jika ditelusuri
akar historis (genealogi) nya, sejatinya persoalan dimaksud menjadi di antara
agenda terpenting dari misi kenabian Muhammad s.a.w. Bahkan, jika boleh
dikatakan, merupakan esensi dari substansi utama Islam sendiri. Ini karena tujuan
dari diturunkannya Islam sebagai kiblat pemikiran dan keimanan manusia adalah
dalam rangka menciptakan umat terbaik (khairu ummatin) yang selain didasarkan
pada prinsip ke-Esa-an Tuhan (tauhid), juga berasaskan pada nilai kesetaraan dan
keadilan.240
Konsep keadilan Tuhan al-Maturidi didasarkan pada keyakinan bahwa
Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana yang dapat dibuktikan lewat alam semesta.
Keadilan-Nya menurut al-Maturidi, adalah dengan tidak dimonopolinya perbuatan
di mana Dia memberi kebebasan berkehendak (masyi‟ah) kepada manusia dalam
menentukan pilihan atas perbuatannya. Adanya ruang memilih inilahyang
menjadikan wajar jika manusiaakan dikenai pertanggung jawaban: Sebuah
penilaian atas penggunaan daya (istita‟a) Tuhan pada dirinya. Sekalipun
demikian, kebebasan dimaksud bukan tanpa batasan. Manusia pada kodratnya
240
Karen Armstrong, 2002. Islam: A Short History, New York: Modern Library Paperback
Edition.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
104
tetaplah memiliki keterbutuhan akan Tuhan yang disebabkan keterbatasan
kemampuannya. Kenyataan ini dalam konsepsi Islam disebut sebagai kesadaran
ketersituasian manusia sebagai ciptaan dan khalifah-Nya (hamba).
Oleh karena Tuhan Maha Bijaksana, maka balasan atas kebaikan mestilah
berbeda ukurannya dari balasan atas dosa. Pahala boleh dilipat-gandakan, tetapi
tidak pada hukuman (siksa). Pada konteks ini, al-Maturidi juga meyakini jika
Tuhan tidak akan menyamakan siksaan yang akan diterima orang beriman
(Mukmin) dengan mereka yang ingkar (Kafir) sekalipun sama-sama berdosa.
Akhirnya, konsep keadilan Tuhan al-Maturidi dimaksudkan untuk bentuk
pengajaran terhadap manusia agar tidak menjadi hakim bagi tindakan dan
perbuatan sesamanya. Baik dan buruk dengan arti kesesuaiannya atau
ketidaksesuaiannya terhadap tabiat (selera) dan dalam arti sifat terpuji (kamāl)
atau sifat tercela (naqsh) adalah bersifat rasional („aqliy). Sedangkan (baik dan
buruk) dengan pengertian adanya konsekuensi pujian dan cacian seketika (di
dunia) dan konsekuensi (pahala dan) siksa kelak (di akhirat), adalah bersifat
syar„I.
C. Keadilan Menurut Filsafat Hukum Umum
1. Konsep Keadilan
Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah
dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu
terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama
obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni
kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti
jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran,
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
105
nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu
sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia,
yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari
sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.241
a. Klasik
Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan “the search for justice”.242
Teori-teori ini menyangkut hak dan
kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Salah satu diantara
teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang
menekankan pada harmoni atau keselarasan. Selanjutnya teori keadilan Aristoteles
dalam bukunya nicomachean ethics, kemudian teori keadilan sosial John Rawl
dalam bukunya a theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen
dalam bukunya general theory of law and state. Berikut kami paparkan beberapa
teori tersebut:
1). Teori Keadilan Plato
Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual
dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai
keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan
itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: “let us enquire first what it is the
cities, then wewill examine it in the single man, looking for the likeness of the
241
Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai
Landasan Pembinaan Hukum Nasional, Disertasi. (Surabaya: Universitas Airlangga 1998), 45. 242
Ibid, 24. Plato mendefinisikan keadilan sebagai thesupreme virtue of the good state, sedang
orang yang adil adalah the self diciplined man whosepassions are controlled by reason, Bagi
Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata
hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga
kesatuannya.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
106
larger in the shape of the smaller”.243
Walaupun Plato mengatakan demikian,
bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara.
Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang
memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu
masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota
melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang
selaras baginya.
Konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan
konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato
mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan
filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai
obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya
sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada.244
Alam
nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang
di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.
Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan
norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti
dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang
menguasai diri sendiri.245
Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada
243
Plato mengatakan bahwa hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara
ketertiban dan menjaga stabilitas negara, akan tetapi yang paling pokok adalah untuk
membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari
negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral
dari setiap warga masyarakat. Lihat The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Sumber
Sukses. 1982), 22. 244
J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles, (Jakarta: Rajawali Press. 1993), 92. 245
Ibid.,102.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
107
kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah
kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.
2). Teori Keadilan Aritoteles
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya
nichomacheanethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku
nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,
berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan.246
Aristoteles membagi Keadilan kedalam dua macam keadilan, keadilan
distributief dan keadilan commutatief. Keadilan distributif ialah keadilan yang
memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan yang
menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya
proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan
apa yang menjadi haknya secara proporsional.
Sedangkan keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada
setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan
peranan tukar menukar barang dan jasa.247
Keadilan distributif menurut
Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain
yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil boleh
jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya
bagi masyarakat.248
Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat
246
L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh
enam, 1996), 11-12. 247
Carl Joachim Friedrich…, 25. 248
Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, 2009, Volume 6
Nomor 1, 135.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
108
ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah
kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara
dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan
kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam
merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.
3). Teori Keadilan Hans Kelsen
Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state,
berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil
apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan
sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.249
Sebagai aliran positivisme
Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir
dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau
kehendak Tuhan.250
Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu
keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang
lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari
penalaran manusia atau kehendak Tuhan.251
Hans Kelsen mengakui juga
kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan
249
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien,
(Bandung: Nusa Media, 2011), 7. 250
Ibid, 9. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat
subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan
kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin
individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh
penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi,
seperti kebutuhan sandang pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang
manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan
rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional
dan oleh sebab itu bersifat subjektif. 251
Ibid, 14.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
109
menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.252
Lebih lanjut, ada
dua hal lagi tentang konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu:
1. Pertama, konsep keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari
cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat
berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya
menimbulkan suatu konflik kepentingan.;
2. Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar
suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen
pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum
adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan
umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak
diterapkan pada kasus lain yang serupa.253
Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum
nasional Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat
dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional
lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat
terhadap materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.254
b. Modern
Konsep keadilan pada zaman modern diwarnai dengan berkembangnya
pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme
yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abab ke-XVII Masehi.
Aliran ini mendasarkan pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa
khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang
politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin
252
Ibid. Menurut Hans Kelsen dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan
karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia
ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang
mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang
pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang
kedua dunia ide yang tidak tampak. 253
Ibid, 71. 254
Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2000), 50.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
110
tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan
individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada
kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.255
Dalam
konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita
toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah
ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri.
Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama,
manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan
yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya
sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu
ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar
manusia diwujudkan. Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme
menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka.
Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan
kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang
sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan
kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.
Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin
dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memperioritaskan
kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang
prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan
dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.256
Bagi
penentang utilitrian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa
255
Lyman Tower Sargent, Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, (Jakarta: Erlangga. 1987), 63. 256
John Rawls, A Theory of Justice, (Massachussets: The Bellnap Press of Havard University
Press. 1971), 43.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
111
hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang
lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. oleh karena itu dalam suatu
masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah,
hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik
ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.257
Menurut Hampstead serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus
bahwa negara diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan
distributif.258
Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang
atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total
distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang
tentu tidak ada tempat bagi negara melakukan campur tangan, apalagi memberi
rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak
diantara warga negara. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga
terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan
tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.
Dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli,
pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan
pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal di
atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai:
a. the constant and perpetual disposition torender every man his due;
257
Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan
individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa
kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan
pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap
moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya
negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi
negara itu juga merupakan ajaran moral. Lihat John Rawls, A Theory of Justice, (Massachussets:
The Bellnap Press of Havard University Press. 1971), 48. 258
Lord Lloyd of Hampstead & MDA Preeman, Introduction to Jurisprudence, (London: English
Language Book Society. Steven, 1985), 421.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
112
b. the end of civil society;
c. the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of
prejudice and improper influence;
d. all recognized equitable rights as well as technical legal right;
e. the dictate of right according to the consent of mankind generally;
f. conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing.259
Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang
mendefinisikan keadilan sebagai: redressing a wrong, finding a balance between
legitimate but conflicting interest.260
Definisi ini menggambarkan bahwa nilai
keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan
yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman
untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Teori lain yang menyatakan
bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang
dengan tegas menyatakan “lex injusta non est lex” yaitu hukum yang tidak adil
bukanlah hukum. Sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap
orang hak perlindungan dan pembelaan diri.261
2.Bentuk-bentuk Keadilan
Dalam bentuknya, keadilan itu tidak berarti semuanya harus sama, tetapi
saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Keadilan adalah keseimbangan yang
harmonis antara berbagai hal yang merupakan elemen masyarakat dan kehidupan
individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Ada tiga bentuk keadilan menurut
fungsinya, yaitu keadilan distributif dan keadilan retributif dan keadilan
sosial;
259
The Encyclopedia Americana, Volume 16, (New York: Americana corporation, 1972), 263. 260
Rudolf Heimanson, Dictionary of Political Science and Law, (Dobbs Fery: Oceana Publication,
1967), 96. 261
Radbruch & Dabin. The Legal Philosophi, (New York: Harvard University Press, 1950), 22.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
113
a. Keadilan distributif
Keadilan distributif262
berarti memberikan barang-barang kepada setiap
orang sesuai dengan tuntutan yang adil, dan tuntutannya yang adil itu ditentukan
oleh status sosialnya yang sebagian tergantung kepada status yang diterimanya
dari nasib sejarah dalam alam dan masyarakat dan sebagian lagi diperolehnya dari
usaha-usaha sendiri dalam menggiatkan status dan potensi-potensinya.263
Terdapat
dua macam prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formal dan prinsip
material. Prinsip formal dikemukakan oleh Aristoteles yang dirumuskan dengan
kalimat equals ought to be treated equally andunequals may be treated
unequally.264
Keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu.
Keadilan ideal menurutnya adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat
bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam, karena manusia dipandang
sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang.265
Keadilan distributif sudah terdapat pada zaman klasik, dan pada zaman
modern ini menjadi semakin urgen. Hal ini menyebabkan keadilan ini banyak
kesulitannya adalah karena menyangkut masalah berbagi. Persoalannya adalah,
bagaimana membagi hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (benefits and
262
Keadilan distributif merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan
hukum publik secara umum. Keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang,
distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip
kesamaan proporsional. Lihat Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum…, 48. Distribusi berarti
pembagian barang, jasa, dan kesejahteraan secara merata. Keadilan distributif menyangkut hal-
hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lain sebagainya. Hal-hal ini harus dibagi menurut
kesamaan geometris. Lihat Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah,
(Yogyakarta: Kanisius, 2011), Cet. XVIII, 43. 263
Anwar Harjono, Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), 24. 264
Artinya: kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-
kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama. Prinsip ini menolak
diskriminasi. Lihat Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 94. 265
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2009), 48.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
114
burdens) secara fair, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak
ada yang mendapat kurang.266
Keadilan distributif dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya proses konsentrasikekayaan267
dan menciptakan sirkulasi kekayaan
untuk menciptakan tujuan utama ekonomi yang sehat268
secara baik di masyarakat
agar tidak ada orang memonopolinya.269
Kemiskinan dan kelaparan bukanlah
semata-mata diakibatkan oleh kemalasan yang bersifat individual, akan tetapi juga
diakibatkan oleh ketimpangan struktur ekonomi dan sosial yang melahirkan
kesenjangan sehingga ajaran Islam sangat melarang kekayaan hanya terpusat dan
berputar di kalangan kelompok orang kaya.270
Prinsip-prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip formal.
Prinsip-prinsip material menunjuk kepada salah satu aspek relevan yang bisa
menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh pelbagai
orang. Kalau prinsip formal hanya ada satu, prinsip material ada beberapa.
Keadilan distributif terwujud, kalau diberikan kepada:
1. Kepada setiap orang bagian yang sama. Membagi dengan adil adalah
dengan membagi rata kepada semua orang yang berkepentingan diberi
bagian yang sama;
2. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Prinsip ini
menekankan bahwa keadilan sesuai dengan kebutuhan;
3. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Hak merupakan hal yang
penting bagi keadilan pada umumnya;
4. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
5. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat;
266
Antonius Atoshoki Gea, Relasi Dengan Sesama: Character Building II, (Jakarta: Elek Media
Komputindi, 2002), 324. 267
Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-Hasyr (59) ayat 7 yang berbunyi: “...
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”, Kerajaan
Saudi Arabia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Mujamma‟ al-Malik Fahd li Thiba‟at
al-Mush-haf, 1423 H), 916. 268
Azyurmardi Azra, Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, (Jakarta:
Mizan, t.t.), 42. 269
Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kompas Media Nusanta, 2010), 172. 270
Didin Hafidhuddin Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2006), 265.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
115
6. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.271
Kondisi sosial yang ada perlu dicermati dengan seksama agar pemilihan
prinsip keadilan distributif yang akan diterapkan dapat benar-benar menyelesaikan
masalah kesenjangan yang ada. Demikian pula, tujuan yang hendak dicapai perlu
diformulasikan secara tepat sehingga lebih mengena pada sasaran.272
b. Keadilan Retributif
Keadilan retributif merupakan suatu kondisi apabila seseorang mengurangi
status dan tuntutan keadilannya karena tidak memenuhi kewajiban atau karena
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sosial dan alam, di
mana statusnya berakar. Keadilan Retributif yaitu suatu keadilan yang pada
prinsipnya diatur oleh hakim yang menjamin, mengawasi dan memelihara
distribusi ini dari serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan ini juga
mengestablishkan status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang
bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi hak yang hilang kepada
pemiliknya.273
Hukuman merupakan tujuan tersendiri yang ditentukan oleh keadilan
retributif ataukah implikasi negatif dari keadilan distributif yang ditentukannya
sendiri.274
Prinsip keadilan retributif tidak menjadi urusan privat, melainkan
terletak di tangan otoritas, yakni sistem yuridis, yang merupakan wakil dari
271
Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis…, 95- 96. 272
Faturochman, Keadilan Perspektif Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 9. 273
Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. Yudian
Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991), 36. 274
Anwar Harjono, Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), 24. Keadilan retributif bisa diartikan memberi ganjaran atau hukuman yang
sepadan. Lihat Ayub Ranoh, Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis Atas
Kepemimpinan Sukarno, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 192.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
116
masyarakat.275
Keadilan retributif dikatakan efektif bergantung kepada
masyarakat apakah mereka menganggapnya sebagai hukum yang merupakan
ganjaran yang setimpal. Jika terjadi sebaliknya, adalah munculnya argumen main
hakim sendiri, yaitu ancaman yang akan terjadi apabila keadilan retributif tidak
diterapkan oleh negara, yaitu bahwa publik/masyarakat akan mengambil alih
hukum ke dalam tangannya sendiri.276
Fungsi keadilan retributif merupakan
pembayaran kembali atas suatu tindakan pelanggaran hukum. Tujuan pemberian
hukuman untuk memuaskan tuntutan keadilan, untuk mengembalikan keadilan
yang telah dirusak, dan dalam arti luas untuk memenuhi tuntutan moral.277
Asas
manfaat dari keadilan retributif adalah demi membela hak.278
Jadi pemberian
hukuman adalah perbuatan yang adil.279
c. Keadilan Sosial
Keadilan sosial pada hakikatnya merupakan persoalan yuridis, karena
terwujudnya keadilan sosial itu sangat bergantung kepada produk legislasi dan
kebijakan pemerintah yang sensitif dan berpihak kepada kepentingan dan
kebutuhan rakyat merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan
sosial.280
Konsep keadilan sosial menyangkut tidak hanya pada sebagian saja
(particular), sedangkan konsep keadilan itu menyangkut hal yang menyeluruh,
Karena keadilan itu menyangkut banyak hal, antara lain:
275
Shindunata, Kambing Hitam: Teori Rene Girard, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 111. 276
Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan
Pendapat Hakim Konstitusi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 127-128. 277
E. Sumaryono, Etika danHukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta: Kanisius, 2006), Cet. V, 86. 278
Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2009), 112. 279
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum…, 124. 280
Frans Hendra Winata, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,
2009), 9.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
117
1) Pemenuhan hak-hak seseorang, yaitu hak-hak individu;
2) Keadilan itu menyangkut prosedur;
3) Reward and punishment, artinya orang yang baik harus diberi penghargaan
dan orang yang jahat dijatuhi hukuman;
4) Sikap; yaitu sikap sosial dan sikap tidak sosial;
5) Pemberdayaan kaum yang lemah, tertindas, dan tertinggal;
6) Pembagian pendapatan atau kesejahteraan secara merata.
Keadilan sosial hanya menyangkut pada pemberdayaan yang lemah
tertindas dan tertinggal dan pembagian kesejahteraan pendapatan secara merata.281
Itulah keadilan yang tidak pandang bulu. Sebuah cermin keadilan yang tegak
karena dibarengi kekukuhan keimanan, masalah harus sesuai dengan hukum,
menghormati aparat hukum, dan juga setiap penegakan hukum memiliki
konsekuensi keimanan yang besar.282
Salah satu dari asas kehidupan
bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat baik yang melebihi
keadilan (seperti berbuat baik terhadap mereka yang bersalah) akan dapat
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.283
Keadilan harus
ditegakkan, kalau perlu dengan tindakan tegas. Al-Qur'an menggandengkan kata
timbangan (alat ukur yang adil) dengan kata besi yang digunakan sebagai senjata
sebagai isyarat bahwa senjata adalah salah satu cara atau alat untuk menegakkan
keadilan.284
Keadilan sosial merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin
dekat, tapi tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna. Di satu masyarakat,
keadilan sosial bisa terwujud jauh lebih baik daripada di masyarakat lain. Tetapi
281
Azyurmardi Azra, Berderma Untuk Semua…hal. Xxxiv. 282
Yusuf Burhanudin, Saat Tuhan Menyapa Hatimu, (Bandung: Mizania, 2007), Cet. I, 240. 283
Ibid. 284
Muhammad Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Jakarta:
Mizan Pustaka, 2007), 347.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
118
praktis tidak ada satu masyarakat pun di mana tidak ada masalah keadilan
sosial.285
Keadilan sosial merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan
nilai-nilai operasional, selain dari norma dan nilai yang terkandung dalam
Undang-Undang, dimana masyarakat siap untuk menerimanya karena kebiasaan,
inersia,286
atau alasan lain. Berbeda dengan konsep keadilan yang idealis-ilahi,
alam atau rasional, keadilan sosial (sering digunakan untuk menyertakan keadilan
distributif) pada dasarnya berada dalam karakter, bahwa hal itu adalah produk dari
pengalaman dan kebiasaan manusia lebih dari dari alasan apapun.287
Berdasarkan
kriteria yang ada, keadilan dalam konsepsi Barat terbagi menjadi dua kriteria:
yaitu keadilan individual dan keadilan dalam negara.
1) Keadilan Individual, menurut Aristoteles adalah kebajikan pokok yang
harus menjadi keutamaan bagi tiga bagian jiwa manusia yang sekaligus
mengikat kesatuan dari ke tiga bagian jiwa itu. Keadilan individual itu
hanya dapat tercapai lewat penguasaan diri yang rasional, yang dapat
mengendalikan diri kepada dua bagian lainnya, yaitu bagian semangat atau
keberanian dan bagian keinginan atau nafsu. Oleh sebab itu dapatlah
dikatakan bahwa keadilan individual ialah berfungsinya kesadaran
seseorang di mana ia sanggup menguasai diri sesuai dengan panggilan
nuraninya yang ditentukan oleh bakat, kemampuan dan keterampilan.288
2) Keadilan Dalam Negara, Fakta menunjukkan bahwa manusia tidak dapat
memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang begitu banyak, mereka lalu
sepakat untuk bekerja sama sesuai bakat dan kemampuan masing-masing
di suatu tempat yang dialami bersama dan selanjutnya lahirlah apa yang
disebut negara.
285
Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis…, 94. 286
Inersia dalam bidang politik artinya status quo. Status quo dalam ranah politik adalah
penolakan terhadap perubahan. Ditolak karena perubahan dianggap akan memakan waktu,
korban, tenaga, pikiran dan pengulangan yang belum tentu sama baiknya dengan keadaan
sekarang. Status quo juga dijadikan tameng buat para politisi untuk tidak mau kehilangan
keamanan finansial, kekuasaan dan penghormatan yang sudah sangat menyamankan diri dan
partai. http://nurulhabeeba.blogspot.com/2013/01/kosa-kata-inersia_7908.html, diunduh pada 23
Februari 2020. 287
N. Hanif, Islamic Concept of Crime and Justice, (New Delhi: Sarup & Son, 1999), Cet. I, 1. 288
J. H. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 85.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
119
Keadilan dalam negara akan tercapai apabila ketiga unsur dalam negara
dapat berfungsi sebagaimana mestinya: yaitu jika pembagian kerja diatur sesuai
dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap warga negara. Jadi apabila
semua orang dan semua kelas dalam negara dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan kebutuhan serta keinginan manusia terpenuhi dan makmur, maka
dapat dikatakan bahwa ada keadilan dalam negara itu.289
3. Keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Hidup dan kehidupan rnanusia merupakan takdir Allah Swt. Manusia tidak
dapat melepaskan diri dari segala ketetapan Allah. Takdir telah meletakkan
manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, tahapan-
tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk berikhtiar
mempertahankan serta melestarikan hidup dan kehidupannya.290
Dalam
kehidupannya, manusia tidak hanya sebatas hidup, tapi ada beban taklif di
dalamnya yang meliputi hak dan kewajiban dalam seluruh proses kehidupannya.
HAM menjadi dua sisi mata uang yang satu sisi mengedepankan humanisme,
sementara sisi yang lain menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi
pengambil kebijakan. Argumentasi ini muncul karena ma-nusia memiliki hak-hak
alamiah (al-huquq al-thabi`iyah)291
sehingga manusia mempunyai kebebasan
alamiah (hurriyah) yang memunculkan kebebasan individu yang humanis.292
289
Ibid. 290
Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2008), 1. 291
Mulhim Qurban, Qalaya al-Fikr al-Siyasi, fal Huquq al-Tabi‟iyah, (Beirut: al-Muassasah al-
Jamiiyah li al-Dirasah wa al-Nasyar al-Taquzi, tt), 60. 292
Ahmad Khalal Hamad, Hurriyah al Ra‟y fi al-Midan al-Siyasi fi Dzilli Mabda‟ al-Masyruriyah
Baths Muwarin fi al-Dimoqratiyah wa al-Islam (al-Wafa‟ li al-Thaba‟ahwa al-Nasyr wa al-
Tawzi‟ al-Mansurah, tt), 73.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
120
Sementara masyarakat adalah kumpulan individu yang merupakan
makhluk sosial yang memiliki perasaan, pemikiran dan peraturan,293
serta
kebutuhan jasmani. Interaksi ini akan berpeluang terjadinya perselisihan karena
kecenderungan manusia untuk memenuhi nalurinya (gharizah). Oleh karena itu,
dalam pembahasan ini mencoba mengurai tentang bagaimana perspektif Islam
tentang HAM dan HAM bagi umat Islam di Indonesia.
a. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan,
yang merupakan anugerah Allah, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu
gugat oleh siapa pun. Beberapa definisi tentang HAM :
1) HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan
kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang
berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia
memilikinya karena ia manusia (Frans Magnis-Suseno);
2) HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak indivi-dual
yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas manusia. (David
Beentham dan Kevin Boyle);
3) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU no. 39 Th.
1999 tentang HAM dan pasal 1 butir 1 No.26 Th. 2000 tentang pengadilan
HAM).294
Dengan demikian bahwa pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah
hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrati yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut
keberadaannya. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri
pokok hakikat HAM adalah:
293
Taqiyuddi al-Nabhani, Nizam al Islam (ttp, tp, 2001), 32. 294
Bambang Suteng, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Erlangga, 2006), 102.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
121
1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian
dari manusia secara otomatis;
2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa;
3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mampunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau
melanggar HAM.295
Oleh karena itu, HAM bersifat universal yang artinya berlaku di mana
saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil siapapun. Hak-hak tersebut
dibutuhkan individu untuk melindungi diri dan martabat kema-nusiaan, juga
sebagai landasan moral dalam bergaul dengan sesama manusia. Meskipun
demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat sesuka hatinya
ataupun seenaknya.
b. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam
Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi
beberapa konsep. Konsep yang dimaksud yaitu aqidah, ibadah, dan muamalat
yang masing-masing memuat ajaran keimanan, aqidah, ibadah dan muamalat. Di
samping mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama
Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syariat atau fikih.
Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep
tentang hak; Pertama, hak manusia atau huquq al-insan al-dharuriyyah; Kedua,
hak Allah atau huquq Allah.296
Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan.
Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM
menurut perspektif Barat.
295
Mansour Fakih, dkk., Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun
Gerakan HAM, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 42. 296
Abu A`la Al Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: YAPI, 1998), 13.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
122
Dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam;
1. Hak darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang
eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila
hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati;
2. Hak sekunder (hajy), yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan
berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya, hak seseorang
untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan
hilangnya hak hidup;
3. Hak tersier (tahsiny), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak
primer dan sekunder.297
HAM dalam Islam sebenarnya bukan wacana asing, karena HAM dalam
Islam sudah ada 600 tahun sebelum Magna Charta298 dikumandangkan. Pandangan
ini diperkuat dengan pendapat Weeramantry sebagaimana dikutip Bambang Cipto
yang menyatakan bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial,
ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.299
Ajaran Islam
tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-
Qur‟an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif
juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam. HAM dalam
Islam dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Piagam Madinah (al-Dustu>r al-Madi>nah). Adapun ajaran pokok dalam
Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan
sesama, baik pemeluk Islam maupun non Muslim. Kedua, saling
membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka
yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Dan kelima menghormati
kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam
297
Masdar F. Mas‟udi, HAM dalam Islam, dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan,
Pendidikan Kewrganegaraan dan HAM, (Yogyakarta: UII Press, 2002). 298
Para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya
Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja-raja yang tadinya memiliki
kekuasaan absolute (Raja yang menciptakan hukum, tapi dia sendiri tidak terikat dengan hukum
yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di
muka hukum. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih
konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. 299
Bambang Cipto, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan
Berkeadaban, (Yogyakarta: LP3 UMY-The Asia Foundation, tt), 263.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
123
Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat
majemuk di Madinah;
2) Deklarasi Cairo (The Cairo Declaration) yang memuat ketentuan HAM
yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al- Nisa: 58, 105,
107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-
Isra‟: 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12 - 17, al-Taubah: 6); hak
kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah:
221, al-Rum : 21, al-Nisa 1, al-Tahrim : 6); hak keseteraan wanita dan pria
(QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orangtua (QS. al-
Baqarah: 233 dan surah al-Isra: 23-24). Selanjutnya, hak mendapatkan
pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-`Alaq: 1 - 5), hak kebebasan beragama
(QS. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan
mencari suaka (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh
pekerjaan (QS. al-Taubah: 105, al-Baqarah : 286, al-Mulk : 15), hak
memperoleh perla-kuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161,
Ali `Imran : 130), hak kepemilikan (QS. al-Baqarah : 29, al-Nisa : 29), dan
hak tahanan (QS. al-Mumtahanah : 8). Ayat-ayat tersebut yang secara
tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Qur'an tentang HAM dapat
diperluas lagi.300
Dari gambaran di atas, baik deklarasi Madinah maupun deklarasi Cairo,
menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak
Islam ada, sehingga Islam tidak membeda-bedakan latar belakang agama, suku,
budaya, strata sosial dan sebagainya. Namun dalam realitas pelaksanaannya,
HAM dipengaruhi oleh konsep HAM dari Barat yang berorientasi sekuler.
Sehingga menghadapi kenyataan semacam ini ada beberapa tanggapan dari
masyarakat muslim dunia tentang HAM, yaitu:
1. Menolak secara keseluruhan. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka
bahwa syariat bersifat sakral, independen dan sekaligus mengatasi kondisi
historis di mana dan kapan pertama kali diwahyukan dan dalam pandangan
mereka syariah merupakan pandangan hidup yang paling benar dan
sempurna. Karena itu, Islam harus membangun versi HAM-nya sendiri;
2. Menerima secara keseluruhan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan
bahwa HAM PBB dan Perjanjian Internatsional merupakan hasil elaborasi
dan merupakan bagian khazanah kemanusiaan dan tidak perlu ada
justifikasi Islam terhadapnya;
3. Tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanyakeinginan
untuk tetap setia pada syari‟ah di satu sisi ada keinginan untuk
menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional. Kelompok ini
300
Dede Rosyada, dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE
UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 221.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
124
meyakini bahwa, syari‟ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan
landasan hidup. Sementara HAM PBB dapat diakomodasi dengan
beberapa prasyarat.301
Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada al-dlaruriyat al-khamsah
atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-islam (hak-hak asasi manusia
dalam islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang dikemukakan oleh
Imam al-Syathibi302
yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu :
1. Menjaga agama (hifzd al-din). Alasan diwajibkannya berperang dan
berjihad,303 Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan
beribadah;
2. Menjaga jiwa (hifzd al-nafs). Alasan diwajibkannya hukum qis}a>s h,304
yang didasarkan pada QS. al-Baqarah:178-179) diantaranya menjaga
kemuliaan dan kebebasannya. Islam sangat menghormati jiwa;
3. Menjaga akal (hifzd al „aql). Alasan diharamkannya semua benda yang
memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah
atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah dan media
kebahagiaan manusia di dunia dan akhlirat. Dengan akalnya manusia bisa
menjalankan perannya sebagai khalifah fi al-ardl;
4. Menjaga harta (hifzd al-ma>l). Alasan qis}a>s untuk para pencuri dan
diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain
dengan cara bathil lainnya;
5. Menjaga keturunan (hifd al-nasl). Alasan diharamkannya zina305
dan
qazdaf.306
Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap
mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya
untuk menjaga keturunan, harta dan kehormatan.
301
Said Agil Husin al Munawar. Al-Qur‟an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta:
Ciputat Press, 2004), 298-299. 302
Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati (Jakarta: Amza,2009). 303
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) Cet.I, Edisi 3, 473. 304
Secara etimologi qis}a>s h berarti meneliti, menyelidiki dengan seksama, memotong. Dari kata
terakhir ini kemudian dipahami bahwa qis}a>s h adalah persamaan antara tindak kejahatan
dengan sanksi; sanksi dengan ukuran yang setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan
sebagai hak bagi hamba, diturunkan bagi orang yang melakukan tindakan tertentu dan telah
memenuhi syarat serta rukunnya. Satu tindakan diberlakukan atas seorang pelaku, sepadan
dengan tindakan yang telah dilakukannya kepada si korban. Bisa dilihat di Musthafa Az Zarqa,
al-Madkhal li al-Fiqh al-„Am, Jilid I, 404. 305
Ulama mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki
dengan perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun
pernikahan yang menyerupai sah. 306
Qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan Zina dengan tujuan mengatakan/
menunjukkan aib seseorang. Lihat I`a>natuth T}a>libi>n, Juz 4, 149. 306
Kahar Masyhur, “Membina Moral dan Akhlak”, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 68.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
125
Kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat islam
supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas
penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat
dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.
Pertanyaannya adalah apakah hukum-hukum yang ditetapkan Islam seperti qis}a>s,
diyat ,ta’zi >r‘ dan sebagainya itu bertentangan dengan HAM? Semua itu masuk
akal dan tidak perlu diperselisihkan. Bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan
balasan yang setimpal karena kejahatan yang diperbuatnya. Sanksi ini dijatuhkan
untuk orang yang melakukan kejahatan tertentu dan telah memenuhi syarat dan
rukunnya. Jadi dengan adanya hukuman ini maka akan memperkecil gerak
manusia untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
126
BAB III
RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Restorative Justice
Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hukum sebagai
pranata kehidupan bermasyarakat memberikan pengaruh yang sangat kuat
terhadap perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia. Fenomena
menunjukkan munculnya berbagai kontroversi terhadap proses dan putusan sistem
peradilan pidana yang dianggap oleh sebagian pihak, tidak memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Munculnya Konsep restorative justice yang dianggap
sebagai gagasan baru dalam sistem hukum pidana, pada dasarnya memiliki
metode dengan pola tradisional penyelesaian konflik dan kejatahan yang telah
hadir di berbagai kebudayaan sepanjang sejarah manusia.
Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan ruang untuk diterapkannya
konsep restorative justice, yang secara substansial juga tidak bertentangan dengan
nilai-nilai hukum pidana Islam. Oleh karena itu, konsep restorative justice
dianggap sebagai konsep yang tepat dalam proses penyelesaian perkara pidana,
dan lebih efektif untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun
demikian, konstruksi konsep keadilan restoratif perlu disesuaikan dengan sistem
penegakan hukum pidana di Indonesia yang menganut konsep keadilan restitutive
dalam pluralisme budaya.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
127
1. Pengertian Restorative Justice
Restorative justice dilihat banyak orang as a philosophy, a process, an
idea, a theory and an intervention.307
Restorative justice adalah peradilan yang
menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak
pidana. Restorativ justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan
semua pihak (stakeholders).
“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders”.
308
Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal
dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan
korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta
kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Restorative Justice atau
sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model
pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian
perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan
pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung
dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu
sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku
dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau
307
Darrell Fox, Social Welfare and Restorative Justice, Journal Kriminologija Socijalna
Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan
University Department of Applied Social Sciences, hal. 56. 308
lihat dalam http://152.118.58.226 - Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Januari,
2020, 21:00.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
128
tindakan kejahatan lebih lanjut.309
Liebmann juga memberikan rumusan prinsip
dasar restorative justice sebagai berikut:
1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
2. Pelakunpelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka
lakukan;
3. Dialogaantara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
4. Adasupaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang
ditimbulkan;
5. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara
menghindari kejahatan di masa depan;
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu
dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun
pelaku.310
Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh
Toni F. Marshal dalam tulisannya “Restorative Justice an Overview”,311
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a Vision
For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative
justice yaitu:
1. Adanya partisipasi penuh dan consensus;
2. Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat
terjadinya tindak kejahatan;
3. Memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. Mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah
atau terpisah karena tindakan criminal;
5. Memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah
terjadinya tindakan kriminal berikutnya.
309
Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica
Kingsley Publishers, 2007), hal. 25. 310
Ibid. 311
Tony F. Marshall menyatakan: “Restorative Justice is a process whereby all the parties with a
stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath
of the offence and its implication for the future (restorative justice adalah sebuah proses di mana
para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk
menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, bagaimana menyelesaikan akibat dari
pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Lihat Marian Liebmann, Restorative
Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
129
Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep
restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran
hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)
bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.312
Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu
kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian
dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.
Kata kunci dari restorative justice adalah empowerment/pemberdayaan,
bahkan empowerment ini adalah jantungnya restoratif oleh karena itu restorative
justice keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.313
Dalam konsep
tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur
dalam proses pidana. Secara fundamental ide restorative justice hendak mengatur
kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan
melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan mereka,
diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam
proses pidana. Dalam literatur tentang restorative justice, dikatakan bahwa
empowerment berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban,
pelaku dan masyarakat).314
Para sarjana memaknainya sebagai berikut:
“has described empowerment as the action of meeting, discussing and
resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional
needs. To him, empowerment is the power for people to choose between
the different alternatives that are available to resolve one‟s own matter.
The option to make such decisions should be present during the whole
312
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
Justice, Cet I, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 180. 313
C. Barton, Empowerment and Retribution ini Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite
(eds), Restorative Justice: Philosophy to Practice Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot:
Ashgate/Dartmouth, 55-76. 314
Mc Cold menyebut ketiga pihak tersebut sebagai stakeholder perkara pidana.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
130
process.315
Artinya; Pemberdayaan dalam konteks restorative justice
adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau
masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam
penyelesaian masalah pidana. Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan”.
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang
diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan
bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang
dilakukan, serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, hingga keadaan
dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya
peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban,
maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh
kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti
kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami.
Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga
diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya. Terkait dengan tujuan
pemidanaan dengan konsep restorative justice, dapat dilihat beberapa pendapat
sarjana, yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan
ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata
lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak
pidana dan pertanggungjawaban pidana.316
Andi Hamzah menyatakan bahwa
masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana
dan peradilan pidana. Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi
atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu
315
Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, Restorative Justice and the Active
Victim: Exploring the Concept of Empowerment, Journal TEMIDA, Mart 2011, 8-9. 316
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. II, (Bandung: Citra Aditya
Bakti), 2002, hal. 88.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
131
abstrak.317
Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih
berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus
konkret.318
Konsep restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting
dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:
1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak/kurang memberikan
kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that
disempowers individu);
2. Menghilangkan/mengurangi konflik, khususnya antara pelaku dengan
korban dan masyarakat (taking away the conflict from them);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami, sebagai akibat dari
tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve
reparation).319
Praktik dan program restorative justice tercermin pada tujuannya yang
menyikapi tindak pidana dengan cara:
1. Identifying and taking steps to repair harm (mengidentifikasi dan
mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);
2. Involving all stakeholders (melibatkan semua pihak (pelaku, korban dan
mayarakat yang berkepentingan) dan;
3. Transforming the traditional relationship between communities and their
governments in responding to crime; yaitu transformasi dari pola dimana
masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi
pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan
masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.320
Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadap-
hadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau
integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau
masyarakat bukan terhadap negara “Restorative Justice is commonly known as a
317
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Cet. I,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 72. 318
Ibid. 319
Ibid. 320
McCold and Wachtel, Restorative practices, The Inter-national Institute for Restorative
Practices (IIRP), New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal,
Vol. 85-101, 2003, 7.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
132
theory of criminal justice that focuses on crime as an act by an offender against
another individual or community rather than the state”.321
Ada beberapa prinsip
dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan,
pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:
1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial
dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana;
2. Restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada
pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh
pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi
lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu)
dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;
3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan
merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang
telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang
berhak menghukum;
4. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem
peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif
menyelesaikan konflik sosial.
Konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang
terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak
hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan
keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang
paling dirugikan (menderita), di samping juga untuk pertanggungjawaban pelaku.
Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam
konteks restorative justice (keadilan restoratif). Beberapa tipikal dari restorative
justice, antara lain:
1. Victim offender mediation (memediasi antara pelaku dan korban);
2. Conferencing (mempertemukan para pihak);
3. Circles (saling menunjang);
4. Victim assistance (membantu korban);
5. Exoffender assistance (membantu orang yang pernah melakukan
kejahatan);
321
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
133
6. Restitution (memberi ganti rugi/menyembuhkan);
7. Community service (pelayanan masyarakat).322
Konsep restorative justice meliputi pemulihan hubungan antara pihak
korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan
bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai
kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya,
melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-
kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan
konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini
korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.
Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi,
semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan
(punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana
pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan
penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum
dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi
(korban).323
Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi
korban kejahatan. Beberapa negara sudah mulai memikirkan alternatif lain untuk
menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena
ketidakpuasan dan frustasi terhadap penerapan hukum pidana yang ada selama ini,
serta penerapan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang tidak
322
Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica
Kingsley Publishers, 2007), 25. 323
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
8.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
134
memberikan keadilan bagi individu, perlindungan kepada korban, dan tidak
memberikan manfaat kepada masyarakat.
Konsep restorative justice juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta
merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem
hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum
Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam
penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat.
Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum
adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-
pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini
menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran-pikiran
pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan
turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.324
Jadi, tidak bisa
dipisahkan begitu saja penegakan hukum dan pembuatan hukum.
Penegakan hukum harus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum,
agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat.
Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas restitution in integurm,325
bahwa
keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan
324
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), 116. 325
Rudi Hartono, Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM, makalah
Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial Victim Protection. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013, 1.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
135
atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan ke keadaan semula,
untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai, dan aman, yang
merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, agar
perlindungan manusia (justiabelen) terlindungi, sesuai dengan adagium “fiat
justitia et pereat mundus” hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik
dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.
Tentunya, sebagai sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental,326
sedapat mungkin nilai-nilai dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk
dalam hal nilai dan kaidah penegakan hukum.
Restorative justice merupakan fenomena baru dalam penegakan hukum di
Indonesia, yang selama ini dianggap telah merusak keadilan masyarakat dan
dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila. Selama ini kita menyaksikan berbagai
kasus hukum yang terjadi mulai dari seorang nenek yang mencuri mangkok,
seorang nenek yang mencuri satu buah semangka, seorang anak yang mencuri
sandal jepit, seorang anak yang menuntut ibu kandungnya, dan berbagai masalah
hukum lainnya yang sebenarnya sepele dan ringan ataupun perbuatan-perbuatan
yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebenarnya juga dapat diselesaikan
dengan konsep restorative justice tersebut.
2. Konsep Restorative Justice
Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri
sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan
masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa
326
Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003), 58-59.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
136
penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan,
maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat
dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.327
Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk restorative justice, yaitu:328
1. There be a restoration to those who have been injured (Terjadi pemulihan
kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan);
2. The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they
desire (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan
keadaan (restorasi); dan
3. The court systems role is to preserve the public order and the communits
role is to preserve a just peace (Pengadilan berperan untuk menjaga
ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian
yang adil).
Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya
memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya
pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat
dan memelihara perdamaian yang adil. Justice Peace dalam restorative justice
ditempuh dengan restorative conferencing yaitu mempertemukan antara pelaku,
korban dan masyarakat untuk mencari atau memutuskan cara yang terbaik
mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan (decide how best to repair the
harm). Selain itu pertemuan (conferencing) juga dimaksudkan untuk memberi
kesempatan kepada korban untuk menghadapi pelaku guna mengungkapkan
perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya; pelaku dapat
mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah
menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain; pelaku kemudian dapat meminta
maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya,
327
Satjipto Rahardjo…, 30. 328
From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wiki-pedia.org/wiki/Restorative_justice.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
137
memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan
pekerjaan pelayanan.329
Adapun semangat yang terkandung di dalamnya meliputi: search solutions
(mencari solusi); repair (memperbaiki); reconciliation (perdamaian); dan the
rebuilding of relationships (membangun kembali hubungan). Semangat
restorative justice itu kemudian memunculkan standar program sebagai berikut:
1. Encounter, yaitu menciptakan peluang bagi korban, pelaku dan anggota
masyarakat yang ingin melakukannya untuk bertemu membicarakan tindak
pidana dan bagaimana sesudahnya;
2. Amends, yaitu mengharapkan pelaku untuk mengambil langkah-langkah
guna memperbaiki kerugian yang telah disebabkannya termasuk
pemberian ganti rugi;
3. Reintegration, yaitu baik korban maupun pelaku sama-sama dipulihkan/
disembuhkan/diperbaiki, serta berkontribusi sebagai anggota masyarakat;
4. Inclusion, yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang terkait
dengan tindak pidana (all stakeholders) dapat berpartisipasi dalam mencari
pemecahan masalah.330
Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah
diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap
penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.331
Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif
mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima
Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap
ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana
retributif.
329
Morris and Max-well, 2001, Restorative or Community Conferencing, The IIRP, 17. 330
Lihat pula http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative justice. Create opportunities for victims,
offenders and community members who want to do so to meet to discuss the crime and its
aftermath; Expect offenders to take steps to repair the harm they have caused including
restitution; that both victims and offenders are restored to whole, contributing members of
society; Provide opportunities for parties/that all stakeholders in a crime can participate in its
resolution. 331
Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana,
(Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 1.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
138
Konsep dan praktek keadilan restoratif ditemukan juga berasal dari praktek
pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli
suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan
menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders.332
Bahkan Jeff Christian,
seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada
mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan
banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara
yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.333
Pada dasarnya restorative justice mengutamakan makna pertemuan antar
pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti
dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang
perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan restorative justice
adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari
sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian
serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai
hak yang harus diterima.334
Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison
tentang restoratif adalah is a form of conflict resolution and seeks to make it clear
to offender that the behaviour id not condoned (welcomed), at the same time as
being supportive resfectful of the individual.335
Berdasarkan pendapat tersebut,
upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban
caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu
332
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa
Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia, 2010), 196. 333
Ibid. 334
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 247. 335
Adrianus Maliala, Restorative Justice dan Penegakan Hukum, Bahan Kuliah Mahasiswa PTIK
Ang 54/55, Jakarta, 2009.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
139
forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua
belah pihak.
Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan
menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi
peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap
kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan
pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak
(humanisasi). Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa
keadilan restoratif (restorative justice) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:
a) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian
pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
b) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan
rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
c) Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban,
pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi
oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.336
Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya sistem peradilan pidana dapat
dilakukan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tetap menegakan
keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat tiga
model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan
pidana, yaitu:337
1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika
keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari
pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa
bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
2. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar
sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem
336
Mudzakir, Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia, makalah, pada Penataran Nasional Hukum
Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya. 337
Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan
pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana), Disertasi, pada
Universitas Indonesia, 2009, 180-183.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
140
peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana”atau
disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada di luar sistem
peradilan pidana; dan
3. Tetap melibatkan pihak penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari
sistem kuasi, pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar
dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada
kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.
Braithwaite mengemukakan konsep Shaming and Reintegration atau
reintegrative shaming adalah aspek inti dari teori restorative justice yaitu kaitan
dengan pelaku untuk membantu korban dan anggota masyarakat lain dalam
pertanggungjawaban mereka atas perilaku yang tidak bisa diterima. Reintegrative
shaming dimana pelaku menerima tanggung jawab atas tindakan mereka (malu)
dan berusaha untuk menebus kesalahan (reintegrasi) kepada korban dan terkadang
masyarakat.338
Cara yang ditempuh dalam peradilan restoratif jelas kontras
dengan penanganan tindak pidana yang selama ini dilakukan, sebagai
dikemukakan oleh Morris sebagai berikut:
This process is in stark contrast to the established way of addressing crime
which are seen as offences committed against the State, rather than on the
actual victim and community where it occurred. Restorative justice lebih
memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan
mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada
memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah
belah. Kebajikan dan prinsip panduan yang mengikuti dalam restorative
justice harus dilihat tidak secara linear atau hirarkis (yang merupakan cara
dari sistem modern) melainkan sebagai kesatuan dari bagian yang saling
berhubungan.339
Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di
tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu
di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar
kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku,
338
John Brithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, (University, Oxford, 2002). 339
Morris and Max-well, 2001, Restorative or Community Conferencing, The IIRP, 17.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
141
serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari
pengaturan tentang restorative justice secara internasional, jelaslah bahwa
penggunaan restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah
diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).
Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep restorative justice ini telah lama
dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali,
Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain
yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh
seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak).
Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah
mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan
orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki
kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa
Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyarawah
mufakat.
Dengan demikian, restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi
masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai
kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban
dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks restorative
justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi,
ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku.
Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh
masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
142
korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah
tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).
3. Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia
a. Restorative Justice
Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif
merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam
upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai
pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan
adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses
penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan
ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada
kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan
praktik di berbagai negara.340
Konsep dalam Restorative Justice menyangkut
kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi
warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya dan
masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan cara
menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang-
kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.341
Tujuan pemidanaan dalam Restorative Justice adalah untuk mengembalikan
pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab. Beberapa contoh kasus
yang dapat diselesaikan secara Restorative Justice, kecelakaan lalu lintas yang
340
Adrianus Meliala, Power Point presentasi: Restorative Justice, Apa dan Bagaimana? www.adri
anusmeliala.com/files/kuliah/kul 19082009103919.ppt, diakses 15 Januari 2020. 341
Ibid. hal. 4.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
143
menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan
keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator.
Demikian juga pada kasus perkosaan, meskipun bukan gambaran utuh dari
penerapan pendekatan restorative baik pelaku dan keluarga korban, tetapi
keluarga pelaku dan keluarga korban dapat bertemu muka untuk sama-sama
mencapai suatu kesepakatan yaitu menikahkan putra putrinya. Tetapi dalam
kenyataan dilapangan hal tersebut sangat sulit untuk ditempuh, karena
kencenderungan manusia sulit untuk menerima suatu musibah, dan sulit
memaafkan si pelaku kejahatan tersebut.
Restorative Justice dapat digunakan dalam menjatuhkan suatu hukuman
atau sanksi, dimana tujuan pemidanaan haruslah untuk meringankan keluarga
yang ditinggalkan. Sebagai contoh, hukuman bagi si pelaku apabila korban adalah
seorang kepala keluarga yang memiliki seorang anak yang masih bersekolah di
sekolah dasar, hukuman dapat diberikan dengan menanggung biaya sekolah atau
hidup bagi anak yang ditinggalkan atau keluarganya, karena pada saat ayahnya
menjadi korban, maka tulang punggung keluarga hilang. Di negeri Belanda, Turki
dan berbagai Negara lain, perlindungan kepentingan korban telah terintegrasi
dalam sistem peradilan pidana, tidak perlu ada gugatan tersendiri.342
b. Hak Asasi Manusia (HAM).
Setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian,
seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan
dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (selanjutnya disebut
HAM). HAM telah menjadi issue yang mendunia disamping demokrasi dan
342
Ibid, 6.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
144
masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu
perhatian yang serius bagi Negara untuk menghormati, melindungi, membela dan
menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.343
Sejarah
mencatat bahwa ide Bung Hatta ternyata diakomodasikan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 45 yang disyahkan
dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akomodasi tersebut
nampaknya merupakan kompromi agar tidak terjadi perdebatan yang
berkepanjangan yang akhirnya akan merintangi tercapainya rumusan konstitusi itu
sendiri agar Indonesia merdeka.344
Keputusan untuk memberikan tempat yang
terhormat bagi HAM dalam UUD 45 adalah merupakan keputusan politik yang
tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu.
Jaminan terhadap Hak Asasi manusia memang harus dicantumkan secara
ekplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam prakteknya Negara
mudah tergelincir menindas HAM warganegaranya.345
Manusia menurut
kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk
hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain
hak yang secara universal disebut HAM. HAM juga harus dijamin oleh Negara
terhadap setiap individu, baik warga negaranya maupun warga negara asing, tanpa
membedakan ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu. Setiap individu harus
dijamin haknya, karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk
343
Deni Kamaludin Yusuf, Proses Legislasi UU no 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia‟
(HAM), Knowledge Leader, Program Pascasarjana UIN SGD, Bandung, 2010. 344
Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), 2. 345
Jimly Assiddiqie, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai
dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Prenada Media, 2005), vii.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
145
dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat
kemanusiaan dan demi kemanusiaan.346
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM),
lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. UU ini
lahir dari sikap positif Pemerintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB
bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga
negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial
lainnya. Hukum HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah
konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration
of Human Rights). Dalam perkembangannya UDHR diikuti hukum internasional
turunan lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
(ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.
Pandangan filosofis atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah
sebagai berikut:
1) Secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memili hak-
hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks
social;
2) Secara epistimologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar
kemanusiaan berikut kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya,
mesti dibatasi oleh hukum (hukum HAM);
3) Tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materiil yang
mengatur proses penegakan HAM di masyarakat.
346
Anton Beker, dalam St. Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan
Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia, (Atmajaya, Yogyakarta, 1999), 2.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
146
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemerintah
berkewajiban menggaransi hak-hak dasar kemanusiaan warganya melalui sebuah
lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas
HAM). Hal ini dapat kita lihat dalam konsideran UU HAM ini, bahwa hak asasi
manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
c. Konsep Penegakan Hukum Restorative Justice.
Secara konseptual, Restorative Justice berisi gagasan-gagasan dan prinsip-
prinsip seperti, membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan
kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.
Menempatkan pelaku, korban dan masyarkat sebagai “stakeholder” yang bekerja
bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil
bagi semua pihak. Selain itu, untuk mendorong pelaku adalah untuk mendorong
pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang
telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban, yang selanjutnya
membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah
dilakukannya.
Keunggulan dari konsep Restorative Justice adalah: dari sisi korban akan
lebih mampu memberi atau memenuhi secara lebih baik kebutuhan dan rasa puas
dibandingkan dengan proses peradilan. Bagi pelaku; akan mendapatkan
kesempatan meraih kembali kehidupannya secara normal dan menjaga rasa
hormat masyarakat, serta kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri lagi.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
147
Selanjutnya dari pandangan sisi masyarakat, pelaku menjadi kurang berbahaya,
uang yang dipergunakan untuk melaksanakan pidana dapat dipakai untuk
melakukan tindakan preventif atau konstruksi lainnya.347
Terlepas dari aspek-aspek positif, tentu saja konsep ini juga akan menemui
kendala-kendala yang akan dihadapi apabila konsep ini diaplikasikan, kelemahan
dari Restorative Justice bahwa hanya dapat dijalankan pada pelaku yang
mengakui atau diketahui pasti sebagai pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui
perbuatannya sulit sekali untuk dijalankan karena konsep ini memerlukan
kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari pelaku. Selanjutnya dalam hal ini
pembuktian haruslah tetap dijalankan dan proses akan berlanjut pada sistem
peradilan pidana secara normal. Dilematis dari Restorative Justice akan timbul,
karena di Indonesia tujuan hukum masih belum jelas ditafsirkan, maka dari itu sifat
melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Tujuan penegakan hukum
yang sesungguhnya bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban,
kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan langkah-
langkah sosial yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum.
Setiap manusia didunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti
hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan
dan lain-lain hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM).
Pendekatan ini masih banyak diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi
pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi
347
Garry Johnstone, Restorative Justice, (WP, 2002), 2.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
148
kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Pro dan Kontra terhadap konsep
Restorative Justice masih terus bergulir sampai dengan tujuan pemidanaan dari
suatu pemberian sanksi hukuman kepada pelaku memiliki tujuan yang jelas.
Dalam Rancangan Undang-undang KUHP yang baru, disana dijelaskan bahwa
setiap kali hakim memutuskan suatu keputusan hukuman, haruslah dijelaskan
mengenai tujuan pemidanaan tersebut.
B. Hukum Pidana Islam.
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.
Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan Jinayah. Pengertian
fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti
mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul
Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara‟
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.348
Adapun
jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk
dan apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana
yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan
yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau
lainnya.349
Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Pengertian
jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah perbuatan-
348
Abdul Waha>b Khalla>f, Ilmu Us}u>li Al-Fiqh, Ad Da>r Al Kuwaitiyah, cetakan VIII, 1968, hal. 11.
Sebagaimana dikutip dalam H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan
dalam Islam), 7. 349
Abdul Qa>dir ‘Audah, At Tasyri> Al Jina>’iy Al Isla>mi>, Juz I, (Dar Al Kitab Al Araby, Beirut),
67.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
149
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman
had atau ta‟zir.350
Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih jinayah itu
adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang
dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
Pengertian fikih jinayah tersebut di ats sejalan dengan pengertian hukum pidana
menurut hukum positif. Bahwa hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang
mengatur masalah tindak pidana dan hukumnya. Sedangkan pengertian hukuman
sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan syara‟.351
Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih mempunyai arti lebih
umum (luas), yaitu ditunjukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya
dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa
tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fikih yang memuat masalah-masalah
kejahatan, pelanggran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan
kepada pelaku perbuatan disebut Fiqih Jinayah dan bukan istilah Fiqih Jarimah.352
Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang berkaitan dengan masalah
perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang di ambil dari
dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek
350
Abu> Al- Hasan ‘Ali> ibn Muhammad Al-Maward>i, Al Ahka>m As Sult}a>niyah, Mustafa> Al Bab
Al Halabi>, Mesir, Cet- III, 1973, 219. 351
Abdul Qadir Audah…, Juz I, 609. 352
Rahmat Hakim.., 15.”
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
150
pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak
pidana dan uqubah atau hukumannya.353
Istilah jarimah menurut arti bahasa adalah segala sesuatu yang dipandang
tidak baik, dibenci oleh manusia, karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran
dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah, jarimah merupakan
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam dengan hukuman
had atau takzir.354
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, hukum
pidana Islam adalah aturan hukum Islam yang berasal dari nash Alquran maupun
hadis tentang kriminalitas, disertai dengan hukuman ataupun tidak, baik
berkenaan dengan jiwa, agama, kehormatan, nasab, harta, maupun segala hal yang
bertentangan dengan kebenaran atau keadilan.
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila telah
memenuhi dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari
jarimah yaitu sebagai berikut:355
1. Unsur formil (rukun syar‟i), Unsur ini mensyaratkan adanya larangan
dalam syara‟ yang yang disertai hukuman terhadapnya; Artinya, suatu
perbuatan baru dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat apabila
pelanggarannya telah diatur dan ditetapkan ketentuannya. Ketentuan
tersebut mencakup ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah, maupun
ketentuan tentang pelanggaraan atau kejahatan yang dibuat oleh manusia;
2. Unsur materil (rukun maddi), Unsur ini mensyaratkan terwujudnya
perbuatan yang membentuk jarimah. Baik perbuatan itu berupa tindakan
nyata, maupun sikap untuk tidak berbuat. Unsur materil ini dapat diukur
dari niat pelaku, perbuatan pelaku, ataupun akibat yang ditimbulkan dari
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah;
3. Unsur moril (rukun adabi), Unsur ini mensyaratkan kemampuan untuk
dimintai pertanggungjawaban dari diri pelaku, yakni pembuat adalah
seorang mukalaf. Mukalaf ialah seorang muslim yang telah akil balig
(cukup umur), yang dianggap mengetahui hukum dan mampu bertindak
353
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam., Jakarta: Sinar Grafika, cet-
II, 2006, ix. 354
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 9. 355
Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 6.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
151
hukum, baik terkait dengan perintah Allah maupun larangan-
larangannya.356
Dengan demikian, suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila
perbuatan tersebut telah memenuhi ketiga unsur yaitu unsur formil (rukun maddi),
unsur materil (rukun maddi), dan unsur moril (rukun adabi). Namun demikian,
selain unsur umum yang harus terpenuhi, suatu jarimah perlu juga memenuhi
unsur-unsur khusus. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada jarimah
tertentu. Unsur ini sebagai ciri dan pembeda antara bentuk dan jenis jarimah satu
dengan lainnya. Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah
pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi
hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jari>mah hudu>d, jari>mah qis}a>s}-
diyat dan jari>mah ta’zi >r:
a. Jari>mah Hudu>d.
Hudud adalah suatu perbuatan atau sikap untuk tidak berbuat yang
menurut nash, telah ditetapkan larangan atas keharamannya beserta
hukumannya.357
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
had. Hukuman had merupakan hukuman yang ketentuan jenis, macam dan
jumlahnya telah menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan sebagaimana yang dikemukakan
oleh Mahmud Syaltut, yaitu suatu hak dari Allah yang manfaatnya kembali
kepada masyarakat dan tidak terbatas pada seseorang.358
356
Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1968), 67. 357
Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005), 22. 358
Ibid..., 23.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
152
Hukuman had tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau
walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).359
Abdul Qadir Audah
mengatakan bahwa hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh
syara‟ dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa
ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:
1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut
telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak
manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.
Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu:
a) Jarimah zina;
b) Jarimah qadzaf;
c) Jarimah syurb al-khamr;
d) Jarimah pencurian;
e) Jarimah hirabah;
f) Jarimah riddah; dan
g) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).
Dalam jari>mah zina, syurbul khamr, hira>bah, riddah, dan pemberontakan
yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah
pencurian dan qadzaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah,
juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.360
Jarimah hudud terbagi menjadi dua kategori yaitu:
1. Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan
makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang
diperbolehkan dan yang dilarang;”
2. Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan
kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.361
359
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12. 360
Mahmud Syaltut mengatakan bahwa hak allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali
kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Oleh karena hukuman had itu merupakan
hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi
korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Lihat Makhrus
Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12. 361
Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariah Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
153
b. Jari>mah Qis}a>s dan Diyat .
Menurut bahasa qis}a>s berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qis}a>s han
yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.362
Maksud mengikuti disini
yaitu mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Lafal
qis}a>s merupakan bentuk mas}dar, adapun bentuk madhinya adalah qas}as}a yang
memiliki arti memotong. Menurut arti, qis}a>s adalah akibat yang sama yang
dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai
atau menghilangkan anggota badan orang lain.363
Sanksi qis}a>s maupun sanksi yang berupa diyat , merupakan sanksi yang
telah ditentukan batasnya, tidak memiliki batas terendah maupun batas tertinggi.
Sanksi ini dapat dihapuskan apabila korban bisa memaafkan pelaku jarimah atau
dimaafkan oleh korban, wali atau ahli warisnya.364
Artinya, dalam kasus jarimah
qis}a>s dan diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan
pelaku jarimah dengan meniadakan qis}a>s dan menggantinya dengan diyat atau
meniadakan diyat sama sekali. Baik qis}a>s maupun diyat kedua-duanya adalah
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara‟. Perbedaannya dengan hukuman had
adalah bahwa hukuman had merupakan hak allah (hak masyarakat) yang diwakili
oleh negara, sedangkan qis}a>s dan diyat merupakan hak manusia (hak individu).
Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana yang dikemukakan
oleh Mahmu>d Syaltut adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang
tertentu.
362
Ibid. 363
Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 29. 364
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 8.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
154
Qis}a>s adalah hukuman pembalasan atas perbuatan, membunuh seorang
manusia atau menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh korbannya atau
menonaktifkan salah satu dari organ-organ korban atau panca inderanya, maka
akan mendapatkan ancaman hukuman yang sama dengan orang yang disakitinya,
sebagai contoh yang disebutkan salah satu ayat didalam Al-Quran adalah hidup
diganti dengan hidup, mata diganti dengan mata, hidung diganti dengan hidung,
telinga diganti dengan telinga. Namun, qis}a>s ini tidak dapat dihindari yang adalah
hak pribadi. Korban atau keluarga mereka bisa memutuskan secara administrasi
akan menggunakan mekanisme tersebut atau tidak. Namun seiring perkembangan
zaman terdapat yurisprudensi yang mengembangkan teknik untuk menggantikan
qis}a>s , karena qis}a>s disini dijadikan Ultimum Remedium (penjatuhan hukum
pidana dijadikan sebagai upaya terakhir). Maka dari itu Konsiliasi dan
Pengampunan/maaf lebih diutamakan.365
Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qis}a>s dan
diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau
digugurkan oleh korban dan keluarganya dengan adanya perdamaian atau
pengampuanan, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.
Dengan demikian maka ciri dari jarimah qis}a>s dan diyat itu adalah:
1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh
syara‟ dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2) Hukuman tersebut merupakan hak perseoranagan (individu), dalam arti
bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan atau
melakukan perdamaian terhadap pelaku.
Jarimah qis}a>s h dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan
365
Mutaz M. Qafisheh, Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the
Global System, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January-June
2012, 489.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
155
dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:
1) Pembunuhan sengaja;
2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
3) Pembunuhan karena kesalahan;
4) Penganiayaan sengaja; dan
5) Penganiayaan tidak sengaja.366
c. Jari>mah Ta’zi >r
Jari>mah Ta’zi>r adalah jarimah yang jenis dan macamnya tidak secara
tegas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan aturan dan sanksi jari>mah
ta’zi>r ditentukan oleh penguasa atau oleh hakim setempat melalui otoritas yang
diberi wewenang untuk kewenangan tersebut.367
Secara etimologis, lafal ta’zi>r
bermakna mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati,
membantunya, menguatkan dan menolong.368
Secara terminologi ta’zi>r yaitu
hukuman yang bersifat edukatif terhadap perbuatan dosa atau maksiat, yang
hukumannya masih belum diatur oleh syarak. Tujuan hukuman edukatif ditujukan
supaya pelaku dapat menyesali perbuatannya, sehingga di kemudian hari dapat
memperbaiki perilakunya, meninggalkan dan menghentikan jarimahnya untuk
tidak mengulanginya lagi.369
Beberapa definisi ta’zi>r menurut para ahli hukum
pidana Islam antara lain:370
1. Wahbah Zuhaili> memberikan definisi ta’zi>r sebagai hukuman yang
ditetapkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan
tidak pula kafarat;
2. ‘Abdul Qa>dir ‘Audah memberikan pengertian ta’zi>r sebagai pengajaran
yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang
diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat
tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu;
366
Ahmad Wardi Muslich..., Xi. 367
M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 29. 368
Ahmad Wardi Muslich…, 18. 369
Ibid…, 248-249. 370
Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana
Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
156
3. Mawardi memberikan pengertian ta’zi>r sebagai pengedukasian kepada
para pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud. Pemberian hukumannya
berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan dosa dan pelakunya.
Menurutnya, ta’zi>r sama dengan hudud yaitu sebagai pengedukasian
dengan tujuan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang
jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dilakukan.371
Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan
hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan
hukuman untuk masing-masing jari>mah ta’zi >r, melainkan hanya menetapkan
sekumpulan hukuman, dari yang ringan sampai yang seberat-beratnya. Di
samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta’zi >r
adalah sebagai berikut;
1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut
belum dikemukakan oleh syara‟ dan ada batas minimal dan maksimal;
2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).
Berbeda dengan jari>mah hudu>d dan qis}a>s maka jari>mah ta’zi >r “tidak
ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jari>mah ta’zi >r “ini
adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisa>s},
yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan diberikannya hak penentuan jari>mah-
jari>mah ta’zi >r dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat
mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa
menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.
Ta’zi>r merupakan sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berupa hukuman
edukasi atas pelanggaran dosa atau maksiat yang bentuk perbuatannya belum ada
ketentuannya, dan tidak termasuk dalam hukuman had maupun kafarat. Sanksi
371
Ibid…, 126.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
157
yang diberikan terhadap jari >mah ta’zi>r dapat berupa hukuman penjara, denda,
kurungan, maupun pencabutan hak-hak tertentu, seperti pemecatan dan
pelarangan untuk meninggalkan suatu tempat misalnya menjadi tahanan rumah
dan tahanan kota. Oleh karena sanksi takzir belum mempunyai batas-batas
hukuman tertentu, yang disebabkan kepastian hukumnya belum ditentukan oleh
syara‟, maka dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi terhadap jari >mah ta’zi>r,
seorang hakim harus melakukannya secara teliti dan memperhatikan petunjuk nas
karena menyangkut kemaslahatan umum.372
2. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam
Hukum Islam diturunkan untuk seluruh manusia, baik orang arab maupun
orang dari etnis lainnya, di barat maupun di timur. Hukum Islam diperuntukkan
bagi seluruh umat manusia yang berbeda-beda, berlainan kebiasaan, tradisi dan
sejarahnya. Hukum Islam adalah hukum bagi seluruh keluarga, kabilah,
masyarakat dan negara. Hukum Islam juga merupakan suatu hukum yang luhur
yang hanya mampu dibayangkan oleh para ahli hukum konvensional, tetapi tidak
bisa diciptakan oleh mereka. Hukum Islam lahir dengan sempurna, tidak ada
kekurangan di dalamnya; bersifat jami‟ (komprehensif), yakni menghukumi setiap
keadaan, dan mani‟, yaitu tidak ada keadaan yang luput dari hukumnya,
mencakup segala perkara individu, masyarakat dan negara. Berikut kami paparkan
asas-asas dasar yang berlaku dalam hukum pidana Islam, yaitu:373
372
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 140. 373
Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana Islam, yaitu; Asas Legalitas, Asas Tidak Berlaku
Surut, Asas Praduga Tak Bersalah, asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Subhat, Asas Amar
Makruf Nahi Munkar, Asas territorial, Asas Material, Asas Moralitas. Lihat M. Nurul Irfan,
Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 32.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
158
a. Asas Legalitas
Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip,
sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata benda) yang
berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai
dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah keabsahan
sesuatu menurut undang-undang.374
Adapun istilah legalitas dalam syari‟at Islam
bisa ditemukan secara detail dalam berbagai ayat, yang secara substansional
menunjukkan adanya asas legalitas.375
Asas legalitas dipopulerkan melalui
ungkapan dalam bahasa latin: Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege
Poenali (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas
ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi
batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari
penyalahgunaan kekuasaan atau keseweenang-wenangan hakim, menjamin
keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang.
Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Asas legalitas dalam Islam bukan
berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Asas legalitas secara
jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang
menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada
manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya
penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Kewajiban yang harus diemban
oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang
374
Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, (Pradnya Paramita,Jakarta, 1969), 63. 375
Abd Qa>dir Audah, At-Tasyri>’ al-Jina>i> al-Isla>mi>, Da>r al-Fikr, Beirut, t.t., 118.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
159
dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam
Islam antara lain: Al-Qur‟an „surat Al-Isra‟ ayat (15):
ى د ت اه ن م ه س ف ن يل د ت ه ي ا نم إ ا ف ه ي ل ع ل ض ي ا نم إ ف لم ض ن وم وازرة زر ت ولرى خ أ نم وزر ك ا وم تم ح ي ب ذ ع ولام رس ث ع ب ن
Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka
Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya
sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan
Kami tidak akan meng‟azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”.
Kaidah Fiqh: Artinya: “Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia
sebelum adanya aturan”. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada
kejahatan-kejahatan hudu>d. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang
pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qis}a>s} dan diyat dengan
diletakanya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa
prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.376
Berdasarkan Asas
legalitas dan kaidah tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya
ketentuan nash,377
maka perbuatan mukalaf tidak bisa dikenai tuntutan atau
pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nash-nash dalam syari‟at Islam
belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan
ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nash
yang mengundangkan.
376
Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta‟zir adalah
yang paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya. Untuk menerapkan asas
legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas
legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu,
keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya. Lihat Ahmad Wardi
Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam., (Jakarta: Sinar Grafika, cet-II, 2006), ix. 377
Ibid…, 316.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
160
b. Asas Tidak Berlaku Surut;
Hukum pidana Islam tidak menganut sistem berlaku surut, artinya
sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bisa
dianggap sebagai suatu jarimah. Asas ini dalam perkembangannya melahirkan
kaidah.378
Tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam. Penerapan hukum
pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan Firman Allah
dalam surat An-Nisa‟ ayat (22):
ف ل س د ق ا م لم إ اء النس ن م م اؤك آب ح ك ن ا م وا ح ك ن ت ول ة ش اح ف ان ك نمه إيل ب س اء اوس ت ق وم
Artinya: “Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan
itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”
Namun, dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku
surut, artinya perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelakunya dikenakan
hukuman walapun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapkannya
pengecualian berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat
berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan memunculkan kehebohan di
kalangan kaum muslimin. Adapun jarimah-jarimah yang diberlakukan surut
antara lain:
1) Jari>mah Qazf (menuduh Zina). Dasar hukumnya adalah firman Allah
dalam surat an-Nuur ayat (4);
ين والمذ ي ن ا ث م وه د ل اج ف اء د ه ش ة ع رب أ ب وا ت أ ي ل ثم ات ن ص ح م ل ا ون رم يا د ب أ ة اد ه ش م وال ل ب ق ت ول ة د ل ول ج ونوأ ق اس ف ل ا م ه ك ئ
Artinya “Mereka yang menuduh wanita-wanita terhormat, kemudian
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
dengan delapan puluh deraan, dan janganlah kamu terima persaksian
mereka untuk selama-lamanya”.
378
Ibid.., 319.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
161
Bahwa nas tersebut diturunkan sesudah terjadinya kedustaan terhadap diri
Aisyah.379
Dengan demikian nas tersebut mempunyai kekuatan berlaku
surut dengan pertimbangan demi ketenangan pada diri korban dan
mengembalikan nama baik mereka serta menghapuskan kesan buruk dari
orang banyak.380
2) Jari>mah Hira>bah (perampokan/begal). Dasar hukumnya adalah firma Allah
dalam surat al-Maidah ayat (33); “sesungguhnya balasan bagi orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka
bumi ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan
bagi mereka di dunia dan di akhirat adalah siksa yang pedih.
Ayat ini turun sesudah terjadinya peristiwa pembantaian terhadap
pengembala unta. Akibat peristiwa tersebut dikenakan sanksi terhadap orang Bani
Ukl (Urainah) yang melakukan kejahatan perampasan harta dan membunuh
pengembala unta sebelum diturunkannya nas Al-qur‟an. Dalam kasus ini
tergambar bahwa hukum pidana Islam dalam jarimah tertentu mempunyai
kekuatan berlaku surut. Tujuan utama dari pemberlakuan surut adalah untuk
memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun, berlakunya surut
tersebut, hanya terbatas pada jarimah-jarimah yang dinilai berbahaya dan sangat
mengganggu kepentingan umum.381
c. Asas Praduga Tak Bersalah;
Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah
asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menurut asas ini, semua
perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas
hukum.382
Selanjutanya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu
perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada
keraguan. Jika ada suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus
379
Kisah ini diambil dari kitab Lu‟Lu‟ wa al-Marjan, 173. 380
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 349. 381
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 59. 382
Ibid…, 60.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
162
dibebaskan. Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam, jauh
sebelum hukum pidana positif mengenalnya. Empat belas abad yang silam Nabi
Muhammad bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman hudud, kapan saja kamu
dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik
salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.383
d. Asas Tidak Sah-nya Hukuman Karena Subhat.
Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman
karena ada keraguan (doubt). Hadits Nabi secara jelas menyatakan: Hindarkan
hudu>d dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan, daripada salah
dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman
harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.384
Abd. Al-Qa>dir
‘Audah memberi contoh tentang keraguan ini dalam kasus pencurian. Misalnya
suatu kecurigaan mengenai pencurian kepemilikan harta bersama. Jika seseorang
mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian
menjadi tidak valid, karena dalam kasus tersebut harta tidak secara khusus
dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari
pelaku perbuatan itu.385
e. Asas Amar Makruf Nahi Munkar
Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada
kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma‟rûf: kebaikan, nahyi:
mencegah, munkar: kejahatan. Abul A‟la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan
383
At-Tirmizi, Sunan At-Tirmi>z>, (Mesir Da>r Al-Bab al-Halabi>, 1963) IV: 33. 384
Subhat adalah maa yusbihu sabit wa laisa bisabit; berarti bertentangan antara unsur formiil‟
dan materiilnya, atau segala hal yang tetap dianggap tidak tetap. Abd. Qadir Audah, at-Tasyri‟‟
al-Jinai.., I: 254. 385
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
163
utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma‟rufat
(kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan
kejahatan-kejahatan.386
Menurut Maududi pengertian ma‟ruf dan munkar sebagai
Istilah ma‟rûfât (jamak dari ma‟rûf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat
yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang
baik. Istilah munkarât (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan
kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal
yang jahat.387
Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi
social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan
penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya
istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap
penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir,
kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama,
kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.388
f. Asas territorial
Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan
melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan
dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha
membagi dunia ini kepada dua bagian: Negeri Islam dan Negeri bukan Islam.
Kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum Islam nampak di
386
Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016), 25. 387
M. Yunan Nasution, Pegangan Hidup (3), (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta,
1981), 30-31. 388
Asmawi, Filsafat Hukum Islam, (Teras, Yogyakarta, 2009), 50.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
164
dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam
kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan
hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada
agama Islam;
2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi
masih tetap dalam agama asal mereka, mereka ini terdiri dari dua bagian:
a. Kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan
tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan
peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
b. Kafir mu‟ahad atau musta‟man, yaitu mereka yang bukan penduduk
negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena
suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal asal mereka.
Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdaasarkan
perjanjian keamanan yang bersifat sementara.
3. Bagi orang musta‟min yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di
negeri Islam, maka adakalanya jarimah yang diperbuatnya menyinggung
hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya
atau menyinggung hak perseorangan seperti jarimah qis}a>s , qadzaf,
penggelapan, perampasan barang dan sebagainya;389
4. Menurut Imam asy-Syafi‟I, Imam Maliki, dan Imam Ahmad (jumhur)
berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan
yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk
dalam daerah yuridiksi dar as-salam, baik pelakunya adalah seorang
muslim, dzimmiy maupun musta‟min. Ini berarti bahwa aturan-aturan
pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum.390
Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang
dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau diwajibkan di
manapun ia berada.
Dapatlah disimpulkan bahwa jari>mah-jari>mah yang diperbuat di negeri
bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau dzimmi), dengan
merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat
dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu.
389
Ibid.., 96. 390
Abdul Qadir Audah.., 287.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
165
Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang
tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.391
g. Asas Material
Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah
segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang
maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had
atau ta’zi >r). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam
mengenal dua macam: hudu>d dan. ta’zi>r. Hudu>d adalah sanksi hukum yang
kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nas, baik al-Qur‟an
maupun hadits. Sementara ta‟zi>r adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak
ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur‟an maupun hadits.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum
pidana yang berbunyi: Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran
atau syubhat.
h. Asas Moralitas
Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam:
1. Asas Adamul ‘Uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima
pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum;
2. Asas Rufiul Qala>m yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak
pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena
pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila;
3. Asas al-Khath wa Nisya>n yang secara harfiah berarti kesalahan dan
kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut
pertanggungan jawab atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan
tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini
didasarkan atas surat al-Baqarah: 286;
391
Ibid.., 98.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
166
4. Asas Suqu>t}’ ‘al-‘Uqu>bah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman.
Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal:
pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan
tugas. kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti:
petugas eksekusi qis}a>s} (algojo), dokter yang melakukan operasi atau
pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum
seperti: membunuh orang dengan alasan membela diri dan sebagainya.
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam H. Pidana Islam.
Pertanggungan jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai teore
kenbaarheid, atau criminal responsibility, atau criminal liability. Maksudnya
adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan
apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Kemampuan tersebut memperlihatkan
kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.
Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan
tersebut.392
Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada
ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula, tiada pemaafan dari suatu
tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu
tindakan yang salah. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari‟at Islam
adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada
perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui
maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.393
Begitu pula bagi orang
yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan
kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu,
392
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
(Jakarta: Storia Grafika, 2002), 250. 393
A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , 119.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
167
seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka
perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.394
Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan
pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemidanaannya harus
diteliti dan dibuktikan bahwa:
1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
(dalam arti luas); dan
5. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-
keaadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.395
Pertanggungjawaban pidana dalam Syari‟at„Islam bisa terjadi, apabila
terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu;
1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan
tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu
asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban
pidana.396
Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak,
orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang
dipaksa atau terpaksa.397
ستيقظ،وعنالصيبحتيبلغ،وعناجملنونحتيعقلرفعالقلمعنثلثة:عنالنائمحتي 394
Abdul Qadīr Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi, 392. 395
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.., 253. 396
Abdul Qādir, Audah.., 392. 397
A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam.., 119.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
168
Artinya: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur
hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak
kecil hingga ia dewasa” (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā‟i, Ibnu Mājah,
Ibnu Jarīr, Ḥākim dan Turmuẓi dari „Aisyah).398
Syari‟at Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya
berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya
harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang
lain, sebagaimana yang terdapat pada ayat al-Qur‟an surat Fatir dan an-Najm yang
berbunyi :
وازرة زر ت رى ول خ أ ل وزر إ ة ل ق ث م دع ت ن ووإ ول ء ي ش ه ن م ل م ي ل ا ه حلرب ق ا ذ ان ك ة ل الصم وا ام ق وأ ب ي غ ال ب م رب مه ون يش ين المذ ر ذ ن ت ا نم إ ن وم
ى زكم ى ت زكم ت اي نم إ ف ه س ف ن يو ل ص م ال للمه ا ل إ
Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan
Hukum. Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat
mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Dengan demikian, apabila terjadi
perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang
bertindak atas namanya, maka orang-orang (para pengurusnya) itulah yang
dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan syakhṣiyyah ma‟nawiyyah yang
bertanggung jawab melainkan syakhṣiyyah ḥaqīqiyyah.399
a. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana
Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya
perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu
398
Jalāludīin,, Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi‟uṣ-Ṣagīr (Bairut: Dār al Fikr. t.th),
Juz 2, 24. 399
A. Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, 76.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
169
perbuatan yang syara‟ melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu
perbuatan yang syara‟ memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan
hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus
terpenuhi dua syarat yaitu „al-idrāk‟ (mengetahui) dan „Ikhtiyār‟ (pilihan).
Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban
pidana.400
Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka
pertanggungjawabannya pun bertingkat-bertingkat sesuai dengan tingkatan
perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh
kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan qosad (niat)nya. Perbuatan yang
melawan hukum itu adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan.
Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (al-
amdi) dan menyerupai sengaja (Syibhu al-amdi). Sedangkan kekeliruan juga
terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (al-khaṭa‟) dan perbuatan
yang disamakan dengan kekeliruan (mā jarā majrā al-khaṭa‟).401
Tingkatan
pertanggungjawaban pidana itu;
1. Sengaja (al-amdi), yaitu pelaku tindak pidana berniat dengan secara sadar
dan sengaja untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau
perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan
demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu
diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Bagitu pula dengan
tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta
dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan
perrtanggungjawaban pidana.402
2. Menyerupai sengaja (Syibhu al-amdi), Perbuatan ini (Syibhu al-amdi )
hanya terdapat dalam jarīmah pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan
Syibhu al-amdi ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam
Malik tidak mengenal istilah Syibhu al-amdi dalam jarīmah pembunuhan
400
Abdul Qadīr, Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi, 402. 401
Ibid.., 405. 402
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
170
atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur‟ān hanya menyebutkan
pembunuhan sengaja (Qatlu al-amdi ) dan pembunuhan keliru (Qatlu al-
khaṭha‟). Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya
dipandang marjuh. Pengertian Syibhu al-amdi dalam pembunuhan adalah
bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi
akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu
yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban.
3. Keliru (al-khaṭa‟); Pengertian keliru (al-khatha‟) adalah terjadinya suatu
perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan
hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan
adakalanya terdapat pada niatnya;
4. Keadaan yang disamakan dengan keliru (mā jarā majrā al-khaṭā); Ada
dua bentuk perbuatan yang yang disamakan dengan kekeliruan:
a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang
melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuan
nya dan sebagai akibat kelalaiannya;
b) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan
hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya.
Pertanggungjawaban perbuatan pidana yang disamakan dengan kekeliruan
(mā jarā majrā al-khaṭā’) lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam
keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak
pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.403
b. Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana
Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pertanggungjawaban pidana,
yaitu:
1. Tidak tahu;
2. Lupa;
3. Keliru; dan
4. Rela menjadi obyek jarimah atas pertanggungjawaban pidana.
Pertama, Faktor Tidak Tahu. Ketentuan yang berlaku dalam Syari‟at Islam
adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia
mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Oleh karena
403
Ibid.., 407.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
171
itu, para fuqoha‟ menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan
tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum.404
Kedua, Faktor Lupa. Lupa ialah tidak tersilapnya sesuatu pada saat
dibutuhkan.“Lupa” selalu digandengkan dengan keliru. Dalam membicarakan
hukum lupa ini para fuqoha>‟ terbagi kepada dua golongan; Golongan pertama;
menyatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah
maupun urusan pidana. Mereka berpegang pada prinsip umum yang menyatakan
bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak
berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Seperti pada ayat; “Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah.... (Q.S. Al
Baqarah: 286). Begitu juga dalam Hadis nabi Saw; “Dihapuskan ketentuan untuk
ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa”(H.R. Ṭabrāni dari
Ṡaubān).405
Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata.
Golongan kedua; menyatakan bahwa lupa hanya menjadi hapusnya hukuman
akhirat. Untuk hukuman-hukuman di dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya
hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak
Allah.406
Ketiga, Faktor Keliru. Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar
kehendak pelaku. Jarīmah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan
404
عفيلميتعناخلطأوالنسيان،ومااستكرهواعليه Para fuqoha dapat menerima alasan tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan
tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam
dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslimin. Pemaafan terhadap orang-orang
tersebut bukan pengecualian melainkan ketetapan hukum Islam yang melarang memberikan
hukuman kepada orang yang tidak mengetahui larangan, sehingga pengetahuan itu diperolehnya.
Lihat A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 139. 405
Jalāludīin, Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Sayuṭi, Al-Jāmi‟uṣ-Ṣagīr, Juz 2, (Bairut: Dār al Fikr,
t.th), 24. 406
Abdul Qadīr Audah, At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi, 438-439.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
172
perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena
kelalaian dan kekurang hati-hatian. Hanya saja yang membedakannya adalah segi
pertanggungjawabannya. Namun demikian, hapusnya pertanggungjawaban pidana
dari perbuatan keliru tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban perdata,‟„karena
menurut Syari‟at“Islam jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan
(ma’ṣu>m).407
Keempat, Rela Menjadi Objek Jarīmah atas Pertanggungjawaban Pidana.
Menurut Syari‟at Islam, kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek
jarīmah tidak dapat mengubah sifat jarīmah itu (tetap dilarang) dan tidak
mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat
menghapuskan salah satu unsur jarīmah tersebut, Misalnya dalam jarīmah
pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa
persetujuan, apabila pemilik harta tersebut menyetujui pengambilan hartanya,
pengambilan tersebut adalah mubah bukan jarīmah. Perbuatan yang berkaitan
dengan jarīmah itu ada tiga macam, yaitu;
1. Perbuatan langsung (al-muba>syarah);
2. Perbuatan sebab (as-sabab);dan
3. Perbuatan syarat (asy-syarṭ).408
Pemisahan antara ketiga macam perbuatan itu dipandang penting karena
untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya dan mana yang bukan pelaku.
Perbuatan langsung (al-mubasyaraoh) adalah suatu perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan
407
A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 141. 408
Abdul Qadīr Audah..., 450.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
173
jarīmah, dan sekaligus menjadi illat bagi jarīmah tersebut. Perbuatan sebab (as-
sabab) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung
namun menggunakan media yang dapat menimbulkan terjadinya jarīmah, dan
perbuatan itu menjadi illat bagi jarīmah tersebut. Misalnya persaksian palsu atas
orang yang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan.
Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarīmah dan
tidak menjadi illat-nya. Misalnya seseorang membuat sumur untuk keperluan
sehari-hari, tetapi kemudian digunakan oleh orang lain (orang kedua) untuk
menjerumuskan orang ketiga sehingga ia mati.
c. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana
Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yaitu yang tercantum di
dalam undang-undang dan yang terdapat diluar undang-undang diperkenalkan
oleh yurisprudensi dan doktrin. Undang-undang dalam arti material meliputi
Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang lebih rendah lainnya, sedangkan dalam
hukum pidana Islam menjalankan ketentuan undang-undang itu, bukan semata-
mata undang-undang yang dibuat oleh Ulil Amri, melainkan undang-undang yang
bersumber dari Allah sebagai Syari‟at yang harus dipatuhi oleh umat Islam.
Secara konkrit perbuatan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana Islam adalah;409
1. Menjalankan ketentuan syari‟at;
2. Menjalankan perintah jabatan;
3. Keadaan terpaksa;
4. Pembelaan diri;
5. Pemaafan;
6. Meninggalnya pelaku;
409
Haliman, Hukum Pidana Syāri ah Islam Menurut Ajaran Ahlussunah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1970), Cet ke-1, 168.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
174
7. Tobat;
8. Kadaluarsa;
9. Pendidikan dan pengajaran;
10. Pengobatan;
11. Olah raga;
12. Hapusnya jaminan keselamatan;
13. Hilangnya anggota badan dan/atau meninggalnya pelaku.
Berikut akan kami uraikan alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana
tersebut sebagai berikut:
Pertama, Menjalankan ketentuan Syari‟at. Kewajiban patuh kepada Allah,
Rasul dan Ulil Amri membawa konsekwensi kewajiban menegakkan
kepemimpinan Ulil Amri dan menegakkan hukum Syari‟at.410
Oleh sebab itu,
mendirikan suatu badan peradilan adalah fardhu dan harus dilaksanakan.411
Dalam
menyelesaikan suatu kasus hukum, maka perlu ada penegak hukum yakni hakim
yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.
Hakim adalah orang yang diangkat oleh Ulil Amri untuk melaksanakan tugas
tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin berkewajiban taat kepada keputusan
hakim selaku Ulil Amri.412
Kedua, Karena perintah jabatan. Kewajiban taat kepada Ulil Amri (Q.S An-
Nisā‟: 5) bukan tanpa ada batas, karena taat kepada Ulil Amri itu bukan semata-
mata taat kepada penguasanya, melainkan taat kepada undang-undang Allah.
Pembatasan ketaatan kepada Ulil Amri ini didasarkan kepada hadis; “Tidak ada
ketaatan kepada seorang mahluk dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah”
410
Ibid. 411
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004), Cet
ke-1, 58. 412
Ibid.., 59.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
175
(H.R. Aḥmad dan Ḥākim).413
Dalam hadis yang lain; “Tidak ada ketaatan kepada
seseorang dalam hal yang maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah dalam hal-
hal yang baik” (H.R. Bukhāri, Muslim, Abū Dāwūd dan Nasā‟i).414
Ketiga, Keadaan Terpaksa. Paksaan adalah suatu keadaan yang dilakukan
oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang
diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari
adanya ancaman itu pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali
mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa415
Sehingga orang
tersebut lepas dari kerelaan dan tidak ada kemauan bebas dalam menentukan
pilihan.416
Keempat, Pembelaan diri. Siapa saja yang berperang di jalan Allah baik ia
membunuh atau dibunuh, ia akan memperoleh ganjaran akhirat berupa surga yang
nikmat. Ketentuan ini, menunjukkan bahwa orang yang membunuh di jalan Allah
adalah bukan merupakan tindak pidana dan karenanya perbuatan tersebut
dikecualikan dari hukuman.417
Orang yang mati atau terbunuh di medan perang
itu disebut mati syāhid dan orangnya disebut syāhid (Q.S. At-Taubah: 111).
Adapun syarat-syarat pembelaan diri adalah:
413
Jala>luddi>n Abdurrohma>n bin Abi> Bakr al-Sayut}i>, Al-Ja>mi’ aṣ-Sagi>r, 203. 414
Ibid.., 203. 415
A. Wardi Muslich...,119. 416
Suatu perbuatan dikatakan terpaksa apabila terpenuhi empat syarat, yaitu; Pertama, Ancaman
yang menyertai pemaksaan adalah berat sehingga dapat menghilangkan kerelaan, seperti
ancaman dibunuh, dipukul dengan pukulan yang berat, dikurung dalam waktu yang lama dan
sebagainya; Kedua, Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, jika orang yang
dipaksa tidak melaksanakan keinginan si pemaksa; Ketiga, Orang yang memaksa mempunyai
kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa
atau petugas tertentu. Apabila orang yang memaksa tidak memiliki kemampuan untuk
mewujudkan ancamannya, dalam hal ini tidak ada paksaan; Keempat, Pada orang yang
menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan
terjadi, kalau ia tidak memenuhi tuntutannya. Lihat Makhrus Munajat.., 63-64. 417
Muslim bin al Hajjāj al-Qusyairy al-Naisābūriy, Ṣaḥiḥ Muslim, (Semarang: Karya Thoha Putra.
t.th), Juz 1, 70.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
176
1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum, serangan itu harus
perbuatan jarīmah dan pelakunya tidak perlu dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana;
2. Penyerangan harus terjadi seketika, artinya pembelaan baru terdapat
apabila benar-benar telah terjadi penyerangan atau diduga dengan kuat
akan terjadi;
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakan serangan kecuali harus menyerang;
4. Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang boleh
dipakai, tidak berlebih-lebihan. Dalam hal pembelaaan yang melampaui
batas, tentu hal itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman;418
5. Syubhāt. Abdul Qādir Audah mendefinisikan syubhāt adalah sesuatu yang
pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap. Dalam kaitannya
dengan hukum pidana Islam, maka perbuatan itu dianggap secara formil
ada tetapi dari segi material tidak ada.419
Haliman mengemukakan bahwa
syubhāt itu berarti serupa, keserupaan, atau hal yang seakan-akan, yang
juga dapat berarti yang samar-samar.420
Kelima, Pema‟afan. Pada dasarnya pemaafan tidak dapat menggugurkan
hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan tindak pidana itu ada
yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka
ada pula pengecualian hukuman itu. Tindak pidana yang mendapatkan
pengeculaian hukuman itu, apabila tindak pidana itu berkaitan dengan hak
perorangan, terutama pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman qiṣāṣ,
yakni tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik dilakukan dengan
sengaja atau dilakukan dengan kekeliruan, (Q.S. Al Baqarah : 178).
ى ل ت ق ل ا ف اص ص ق ال م ك ي ل ع ب ت ك وا ن آم ين المذ ا ي ه أ ا ي د ب ع ل وا الر ب الرى ث والن د ب ع ل ا ى ب ث الن ع ب م ال ب اع ب ات ف ء ي ش يه خ أ ن م ه ل ي ف ع ن م ف روف
ان س ح إ ب ه ي ل إ ء ا د ذ وأ ورحة م ربك ن م يف تف ك ى ل د ت اع ن م ذ ف د ع ب ك ليم ل أ اب ذ ع ه ل ف
418
A. Hanafi…, 160-161. 419
Abdul Qadīr „Audah…, 209. 420
Haliman.., 195.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
177
Keenam, Meninggalnya si Pelaku. Meninggalnya si pelaku menjadi sebab
hapusnya sanksi hukum, meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Apabila
sanksi itu tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak
menyebabkan hapusnya hukuman ta,zīr itu, seperti sanksi denda, perampasan dan
pengrusakan hartanya, karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si
pelaku telah meninggal.421
Ketujuh, Tobat. Tobat bisa menghapuskan sanksi hukum baik jarīmah
yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarīmah yang berhubungan dengan hak
Allah/hak masyarakat atau hak Adami/perorangan. Sedangkan bila berkaitan
dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi yaitu melepaskan
kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.422
Kedelapan, Kadaluwarsa. Kadaluwarsa adalah lewatnya waktu tertentu
setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan
tanpa dilaksanakan hukuman.423
Apakah kadaluwarsa dapat menghapuskan
hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqoha tidak menghapuskan,
sedangkan fuqoha yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya
sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarīmah. Untuk itu ada dua teori,
yaitu;
1) Suatu hukuman atau jarīmah tidak gugur dengan kadulawarsa, selama
hukuman atau jarīmah itu bukan jarīmah ta,zīr. Apabila jarīmah ta,zīr
berlaku prinsip kadulawarsa jika dipandang perlu oleh penguasa untuk
mewujudkan kemaslahatan umum. Teori ini dikemukakan oleh Imam
Malik, Syafi‟i dan Ahmad.
2) Mengakui adanya prinsip kadulawarsa untuk jarīmah ta,zīr, namun
mengakui adanya prinsip kadulawarsa untuk jarīmah qiṣāṣ-diyāt dan satu
421
Ibid.., 223-224. 422
Ibid.., 228. 423
Ibid.., 233.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
178
jarīmah hudūd yaitu qozaf. Teori ini pendapatnya Imam Abŭ Hanīfah dan
para muridnya.424
Alasan jumhur selain Imam Abŭ Hanīfah hukuman hudūd tidak hapus
dengan kadulawarsa antara lain:
1. Ulil Amri tidak memiliki hak untuk memaafkan dalam kasus jarīmah
hudūd, baik terhadap kesalahan maupun sanksinya;
2. Bahwa mengakhirkan pemberian persaksian itu sangat mungkin, baik
karena uzur atau gaibnya saksi had tidak hapus karena adanya
kemungkinan, sebab apabila had dapat hapus karena adanya berbagai
kemungkinan itu, maka menjadikan had itu tidak wajib;
3. Diriwayatkan dari Umar bahwa saksi yang menyaksikan kasus jarīmah
hudūd, kemudian tidak memberikan persaksian pada waktu itu, maka
persaksiannya meragukan.
Adapun mengenai batas waktu kadulawarasa, Imam Abŭ Hanīfah tidak
menentukan batas masa kadulawarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan
menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, maka penguasa
negara bisa membuat batas masa kadulawarsa dan menolak setiap keterangan
(persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya
berupa persaksian.425
Kesembilan, Pendidikan dan Pengajaran. Islam memberikan wewenang
kepada suami atas isterinya untuk memberikan pengajaran sebagai hukuman dari
perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman had, seperti meninggalkan suami
tanpa sepengetahuan dan izinnya, terlalu konsumtif terhadap harta dan lain-
lainnya.426
Suami mempunyai hak untuk memberikan hukuman kepada istrinya,
manakala si istri tidak mentaati suami/nusuz berupa menasehati, meninggalkannya
di tempat tidur dan memukulnya (Q.S. An Nisa: 34).
424
A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 234. 425
A. Hanafi.., 256-257. 426
A. Wardi Muslich.., 103.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
179
ى ل ع م ه ض ع ب اللمه ل ضم ف ا ب اء النس ى ل ع ون ومام ق ال الرج ن م وا ق ف ن أ ا وب ض ع ب والم م ان أ ق الات الصم ف اللمه ظ ف ح ا ب ب ي غ ل ل ات ظ اف ح ات ت ون تاف ت واللم
نم وه رب واض ع اج ض م ال ف نم روه ج واه نم وه ظ ع ف نم وزه ش وا ن غ ب ت ل ف م ك ن ع ط أ ن إ ف يل ب س نم ه ي ل يا ع ب ك يا ل ع ان ك اللمه نم إ
Kesepuluh, Pengobatan. Seorang dokter melakukan pengobatan kepada
pasien dengan tujuan agar pasien segera sembuh dari penyakit yang dideritanya,
dan upaya itu dilakukan sesuai dengan kewajiban profesionalnya. Seorang dokter
mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan pengobatan tersebut
sebagai konsekwensi logisnya, seorang dokter tidak dapat dituntut atau dikenakan
pertanggungjawaban pidana karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan,
karena pelaksanaan suatu kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan
objek, yaitu orang yang diobati.
Kesebelas, Olah Raga. Syari‟at Islam menjunjung tinggi dan membolehkan
jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitan
keberanian serta kepahlawanan, melalui kegiatan olah raga seperti pacuan kuda,
panahan, tinju, angkat besi dan sebagainya.
Kedua belas, Hapusnya Jaminan Keselamatan. Hapusnya jaminan
keselamatan disini ialah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau
anggota-anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau
dilukai.427
Tindakan tersebut bisa diadakan apabila dasar-dasar adanya
keselamatan jiwa atau anggota badan telah hapus. Dasar-dasar tersebut ialah Iman
(Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup. Dengan demikian,
427
A. Hanafi.., 75.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
180
jaminan keselamatan bagi seseorang menjadi hapus, apabila ia keluar dari agama
Islam (murtad).
Ketiga belas, Hilangnya anggota badan dan atau meninggalnya si pembuat
jarīmah. Tobat dapat menggugurkan hukuman terutama pada kasus jarīmah
hirobah, meskipun Ulil Amri dibolehkan menjatuhkan hukuman ta‟zīr „bagi
pelaku hirobah ini demi kemaslahatan umum. Apabila si pelaku jarīmah
meninggal dunia, hukuman mati yang ditetapkan kepada si pelaku menjadi batal
pelaksanaannya karena si pelakunya meninggal dunia. Namun hukuman yang
berupa harta benda, diyāt dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.428
C. Restoratif Justice Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia
1. Fleksibilitas H. Pidana Islam
Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme melalui non formal,
seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah
pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali
dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur
peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar
kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Islam. Dalam hukum Islam, mediasi
bisa ditemukan dalam jarimah qisas-diyat , yang sebenarnya terbatas kepada
perkara tertentu saja. Mediasi tidak dikenal dalam hukum pidana modern, sudah
sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana. Hukum pidana Islam
mengenal adanya pemaafan, sebagai salah satu poin penting dalam keadilan
restoratif, khususnya dalam Jarimah qisas/diyat .
428 Abdul Qadīr Audah.., 772.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
181
a. Is}la>h (perdamaian) dalam Hukum Pidana Islam
Peraturan hidup dalam Islam telah ditetapkan melalui sumber hukum yang
mutlak, yaitu Al-Qur‟an sebagai sumber hukum pertama, As-Sunnah sebagai
sumber hukum kedua, ijma‟ ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan
qiyas (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber-sumber hukum Islam
tadi merupakan hierarki dalam sistem Hukum Islam. Hasby Ash-Shiddieqy
mengatakan bahwa hukum dan Islam mempunyai beberapa maziyah
keistimewaan dan beberapa mahsanah keindahan yang menyebabkan hukum
Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat
masyarakat.429
Konsep Is}la>h dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan al’afwu, bahkan
ada beberapa ulama yang menyamakan antara islah dan al’afwu. Namun, ketika
menyimak pernyataan Shahrour mengenai sinonimitas dalam Al-Qur‟an, sejatinya
tidak ada sinonimitas dalam Al-Qur‟an. Anggapan adanya sinonimitas dalam Al-
Qur‟an akan memberi kemungkinan penggantian firman Allah dalam Kitab-Nya
yang mulia dan anggapan adanya tambahan-tambahan di dalamnya, di mana
pengabaiannya tidak akan merubah atau menambah kandungan maknanya
sedikitpun, dan terhadap hal ini sangat tidak mungkin terjadi bagi Allah yang
maha suci.430
Hal ini mengharuskan upaya pencarian perbedaan atau spesifikasi
makna ketika di dalam Al-Qur‟an disebutkan ada kata Is}la>h dan al‟afwu. Untuk
lebih jauh memahami pengertian ishlah secara utuh ada baiknya kita bandingkan
langsung dengan konsep al‟afwu.
429 T.M. hasby Ash-Shiddiqiey, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 119. 430 Muhammad Shahrour, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Judul Asli: Nahwu Usul, Jadidah
Li al Fiqh al Islami, cet. I, (eLSAQ Press, 2004), 256-257.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
182
Is}la>h telah diserap menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti
perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai.431
Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, damai dimaknai sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan,
aman, tentram, keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan kata perdamaian dimaknai
sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan. Mendamaikan dimaknai
mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali; merundingkan supaya ada
persesuaian; menenangkan.432
Sedangkan maaf dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan;
ampun. Pemaafan diartikan proses, perbuatan, cara memaafkan, pengampunan.
Maaf sama dengan ampun.433
Mengacu pada kajian etimologis di atas maka dapat
kita tarik satu perbedaan secara makna bahasa antara islah dan al‟afwu, yaitu
bahwa islah adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan al‟afwu adalah
memaafkan, yang dipersamakan dengan pengampunan.
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Is}la>h merupakan tindakan
mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa yang menjadi kewajiban
umat Islam baik personal maupun sosial. Penekanan Is}la>h ini lebih difokuskan
pada hubungan antar sesama umat manusia dalam rangka memenuhi kewajiban
kepada Allah SWT.434
Bahwa antara Is}la>h dan al‟afwu berbeda secara definisi
maupun konseptual. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa is}la>h merupakan
satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing
pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan
431 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baeey, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994, 274. 432 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cet. Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, 2008, 30 dan 540. 433
Ibid,182-183. 434
Abdul Aziz Dahlan dkk.., 740.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
183
kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian kedua belah pihak. Sedangkan
al‟afwu, adalah media penyelesaian perkara kejahatan qis}a>s dengan melepaskan
hak qis}a>s „dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan di lakukan
qis}a>s .435
Dalam konteks jina>ya>t dan lebih khusus lagi persoalan pembunuhan,
secara implisit menarik satu garis pembeda antara al’afwu dan is}la>h dengan
melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Jikalau inisiatif pemberian
kompensasi terhadap hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah pihak,
maka itu dikatakan is}la>h (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian
kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka
yang demikian itu masuk dalam kategori al‟afwu (pemaafan).436
Pembedaan
antara Is}la>h dan al‟afwu tersebut dapat dikatakan hanya pada tataran konsep saja,
sedangkan dalam praktek, sangat dimungkinkan terjadi persamaan teknis dalam
pelaksanaan antara is}la>h dan al’afwu sebagai satu metode penyelesaian suatu
jarimah. Bahwa Is}la>h merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah
keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup pula dalam
bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama.
Sedangkan al‟afwu merupakan satu konsep penyelesaian perkara praktis berupa
pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan
konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi) atau
tanpa kompensasi.437
435 Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out
Court System,Jakarta : Gratama Publishing, 2011, 290. 436 Abdul Qodir.., 774. 437 Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat.., 292-293.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
184
Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya Is}la>h (perdamaian) dalam
qis}a>s}, sehingga dengan demikian qis}a>s menjadi gugur. Is}la>h (perdamaian) dalam
qis}a>s} ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada diat, sama
dengan diat, atau lebih kecil dari diat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang
(angsuran), dengan jenis diat atau selain jenis diat dengan syarat disetujui
(diterima) oleh pelaku.438
Disinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum
pidana Islam, yaitu aspek restorative justice. Dalam hukum pidana Islam berlaku
hukum qis}a>s}-diyat, hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya
(qis}a>s) dan ini sesuai rasa keadilan korban. 439
Is}la>h (perdamaian) ini statusnya dengan pemaafan, baik dalam hak
pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat
munggugurkan qis}a>s . Perbedaannya dengan pengampunan adalah pengampunan
itu pembebasan qis}a>s tanpa imbalan, sedangkan Is}la>h (perdamaian) adalah
pembebasan dengain imbalan. Memang dimungkinkan pemaafan dari qis}a>s
dengan imbalan diat, seperti dikemukakan Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad,
namun menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu harus dengan persetujuan
pelaku, dan kalau demikian, hal itu harus dngan persetujuan pelaku, dan kalau
demikian, hal itu bukan pemaafan melainkan shulh (perdamaian).440
Orang yang
berhak memberikan memiliki dan memberikan pengampunan atau perdamaian
adalah orang yang memiliki hak qis}a>s . Menurut jumhur ulama yang terdiri atas
438 Ahmad Wardi Muslich.., 163. 439 Topo santoso mengatakan bahwa perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/
keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat
(yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi
kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat
perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses
peradilan pidana. Lihat Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat
dalam wacana dan agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, cet-1, 2003), 93. 440 Ahmad Wardi Muslich.., 163-164.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
185
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad pemilik qis}a>s adalah semua
ahli waris, baik zawil furu>d} maupun ashabah, laki-laki maupun perempuan
dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Akan tetapi menurut Imam Malik,
pemilik hak qis}a>s adalah ashabah laki-laki yang paling dekat derajatnya dengan
korban dan perempuan yang mewaris dengan syarat-syarat tertentu mereka
adaalah mustahik (ahli waris) qis}a>s .441
Apabila mustahik qis}a>s itu hanya seorang diri, dan ia memberikan
pengampuanan atau melakukan perdamaian maka perdamaian dan
pengampunanan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan
demikian, pelaku bebas dari hukuman qis}a>s. Apabila wali korban (mustahik
qis}a>s) menuntut kompensasi dengan diyat, ia wajib membayar diyat atas
persetujuannya menurut Hanafiah dan Malikiyah, atau meskipun tanpa
persetujuannya menurut syafi‟iyah dan Hanabilah.442
Apabila mustahik qis}a>s
terdiri dari beberapa orang, dan salah seorang dari mereka melakukan perdamaian
atau memberikan pengampunan, hukuman qis}a>s h menjadi gugur, dan dengan
demikian pelaku bebas dari hukuman qis}a>s . Hal ini karena qis}a>s itu merupakan
satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi di antara ahli waris. Hanya saja untuk
pembebasan ini, Malikiyah memberikan persyaratan orang yang melakukan
perdamaian atau memberikan pengampunan itu sama derajatnya dengan ahli
waris (mustahik) yang lain, atau lebih tinggi. Dengan demikian, apabila yang
melakukan perdamaian atau memberikan pengampunan itu derajatnya kepada
pelaku lebih rendah daripada mustahik yang lain maka perdamaian atau
441 Abdul al-Qadir Audah, II.., 159. 442 Ahmad Wardi Muslich.., 162.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
186
pemaafannya itu tidak berlaku, dan pelaku belum bebas dari hukumannya
(qis}a>s).443
Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari qis}a>s maupun
diat, pengampuanan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari qis}a>s dan diat
yang kedua-duanya merupakan hak adami (individu). Akan tetapi, oleh karena di
dalam hukum qis}a>s itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak
manusia (individu), penguasa (negara) masih berwenang untuk menjatuhkan
hukuman ta‟zir. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah.
Hukuman ta‟zir menurut malikiyah adalah penjara selama satu tahun dan jilid
(dera) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut syafi‟iyah, hana>bilah, Isha>k,
dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta’zi >r.444
b. Prinsip-Prinsip Is}la>h dalam Hukum Pidana Islam
Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan juga sebagai
perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap
sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan
menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan
antarmanusia. Keadilan harus selalu dilibatkan dalam hubungan satu manusia
dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia tidak
dapat dimungkiri lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi
pemangsa bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu
harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan
443 Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib al Al-Arba‟ah, juz V, Beirut: Dar Al-
fikr, 266. 444 Ibn Rusyd Al-Qurtubi, Bidayah Al-Mujtahid, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 303. Sebagaimana
dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 162.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
187
antarsesama. Berikut kami uraikan beberapa hal terkait prinsip-prinsip
perdamaian (Is}la>h) dalam hukum pidana Islam;
1. Pengungkapan Kebenaran; Is}la>h dalam Islam merupakan satu konsep
utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip
yang harus ada dalam proses islah antara lain; pertama, pengungkapan
kebenaran, kedua, adanya para pihak yang meliputi pihak yang berkonflik
yang dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku, sedangkan pihak
yang lain adalah mediator, ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa
paksaan, dan keempat adalah keseimbangan hak dan kewajiban.445 Ishlah
merupakan satu proses perdamaian dimana peran infrmasi yang benar
sangat besar, yaitu dijadkan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh
masing-masing pihak.446
2. Para Pihak dalam Is}la>h; Para pihak dalam Is}la>h atau perdamaian dapat
diketahui dari al-Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:
ا م ه ن ي واب ح ل ص أ واف ل ت ت ق ا ي ن ؤم م ل ا ن م ان ت ف ائ ط ن وإ
Ayat ini juga mengandung perintah kepada pihak ketiga, maka pada
dasarnya mediator sangat penting, bahkan ketika berposisi sebagai pihak
ketiga, menurut ayat tersebut, hukumnya wajib untuk mendamaikan.447
c. Pihak yang Berkonflik
Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak
yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, para pihak yang benar-
benar memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu
antara pihak-pihak pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan islah adalah satu
proses kesepakatan antar pihak untuk mendapatkan satu kesepahaman sehinga
tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan. Keberadaan pelaku dan korban secara
rinci juga ada syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut :
445 Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat.., 301-301. 446 Ibid.., 302. 447 Ibid.., 303.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
188
Korban, dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung,
yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita
kerugian. Hal ini jelas diterangkan dalam al-Qur‟an surat al-Maidah (45);
س ف الن م نم أ ا يه ف م ه ي ل ع ا ن ب ت وك ن والذ ف الن ب ف والن ي ع ال ب ي ع ل وا س ف الن م ب اص ص ق والروح ن الس ب نم والس ن الذ ب ه ل ارة فم ك و ه ف ه ب ق دم ص ت ن م ف ن وم
ول أ ف اللمه زل ن أ ا ب م ونليك م الظمال م ه ك ئ
Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka
(pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.
Dalam ayat tersebut jelas, bahwa orang yang menderita secara langsung
itulah yang memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Ketika kejahatan yang terjadi
berupa pembunuhan, maka korban yang paling dekat yiatu ahli warislah yag
memiliki hak untuk melakukan ishlah. Selain sebagai korban langsung, korban
yang dapat melakukan islah juga disyaratkan harus dalam keadaan dapat
bertanggung jawab dalam perbuatannya, yaitu bahwa dia sudah dewasa, tidak
dalam keadaan gila, atau dalam keadaan mabuk, atau dalam keadaan tertekan atau
terpaksa.448
Pelaku, dalam Is}la>h harus pelaku yang bertanggung jawab secara pribadi
dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu orang yang jika tidak ada Is}la>h
maka dialah yang akan mendapat hukuman sesuai ketentuan. Pelaku sebagai
448 Dalam proses islah, hanya korban secara langsung lah yang memiliki hakuntuk melakukan
islah, karena korban dalam kerangka publik hanya memiliki hak mendapat kedamaian dan bebas
dari rasa takut dan juga adanya jaminan keamanan. Dan bebas dari rasa takut dan juga adanya
jaminan keamanan. Sedangkan islah berarti selesainya perkara dengan damai, yang artinya telah
ada penginsafan baik dari pelaku maupun korban yang juga berdampak secara publik berupa
hilangnya ketakutan adanya kejahatan tersebut, dan berarti pula pulihnya kembali kedamaian
dalam masyarakat. Lihat Ahmad Djazuli, Fiqh Jinaiyah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
2000, 168.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
189
pihak dalam Is}la>h ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang
menyebabkan kerugian pada pihak korban, yang berarti pula harus ada
pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan
pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang dapat menjadi pihak dalam Is}la>h adalah
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya tersebut.
Mediator, Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah
sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Qur‟an bahwa Allah memerintahkan
untuk mendamaikan sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Bahkan jika
dikaji lebih jauh, maka hukum adanya mediator mendekati wajib, karena secara
langsung diperintahkan dalam bentuk amar. Mediator disini adalah pihak yang
secara independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu
penyelesaian sengketa secara aktif. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan
berdasar asa mas}lahah.449
Is}la>h mestinya harus dimediatori oleh hakim, karena jika tidak, maka tidak
memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama nantinya. Islah
pada dasarnya adalah satu proses peradilan, bukan satu sistem di luar peradilan.
Sementara itu, Saamikh as Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kholiq,
mengungkapkan enam syarat dalam proses al ishlah wal‟afwu anil uqubah yang
dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi. Syarat yang terakhir adalah
harus adanya legitimasi berupa putusan pengadilan agar executable.450
Dengan
449 Adi Sulityono, Mengembangkan Paradigma NonLitigasi di Indonesia, Surakarta: UNS Press,
2006, 401. 450 Enam Syarat yang diajukan oleh Saamikh Sayyid Jaad, yaitu: 1) pengampunan
diberikan oleh pihak yang memang berhak, 2) pihak yang memberikan pengampunan harus
cakap hokum (aqil dan baligh), 3) pengampunan tidak boleh atas dasar paksaan, 4)
pengampunan harus dengan kata-kata atau kalimat yang shorih (jelas), 5) pengampunan diikuti
pemberian ganti rugi (diyat) oleh pelaku kepada korban atau whli warisnya, dan 6)
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
190
kata lain, hakim adalah sebagai pihak yang menguatkan saja atas hasil
perdamaian yang dilakukan para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam
implementasinya.
Is}la>h merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang
didalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam surat Al-
Hujurat ayat 9, jelas dinyatakan bahwa Is}la>h harus diselesaikan atau dilaksanakan
dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah
satu pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam Is}la>h konsistensi keseimbangan para
pihak sangat penting eksistensinya. Karena sifatnya konflik, maka masing-masing
memiliki versi kebenaran sehingga Is}la>h akan menyatukan pandangan mereka
dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai tidak berkepanjangan. Dalam
hal suatu kejahatan dilakukan islah dengan cara kesepakatan pemaafan, maka
harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan.451
Islam mengingatkan bahwa dalam konteks masyarakat, dalam
menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat hendaknya dengan
konsep keadilan sosial juga, yaitu dengan meletakkan suatu pada tempatnya,
artinya menggunakan asas proporsionalitas. Memaafkan yang bersalah dan
memberikan bantuan kepada pemalas, disebut sebagai menggoyahkan sendi-sendi
pengampunan harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar executable. Lihat dalam M.
Abdul Khaliq, Impunitas Kejahatan Masa Silam (Sebuah telaah Menurut Perspektif Hukum
Pidana Islam), Pointer diskusi disampaikan pada forum diskusi Bedah Buku Berjudul Menolak
Impunitas, diselenggarakan oleh LEM FH UII, pada tanggal 27 Februari 2006, 5. Sebagaimana
dikutip dalam Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 307. 451 Menurut Qurais Shihab, adanya aturan mengenai pemaafan adalah keringanan dari Tuhan agar
tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, dan hal ini juga merupakan rahmat dari Allah
bagi keluarga korban atau pelaku sekaligus. Bagi korban dilarang menuntut berlebih yang di luar
kemampuan pelaku, pelaku pun dilarang menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau
mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir
Al Mishbah..., 393.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
191
kehidupan masyarakat, karena hal itu sudah melebihi keadilan sosial itu.452
Relevansinya dalam pembahasan ini adalah bahwa maaf tidak begitu saja dapat
dijadikan satu metode ishlah, harus sangat selektif agar tidak melampaui nilai
keadilan yang itu menggoyahkan sendi kemasyarakatan, dan hanya akan
kontraproduktif terhadap pencapaian perdamaian itu sendiri. Dalam hukum
pidana Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal ishlah,
dengan satu tujuan perdamaian yang sejati, yaitu hilangnya beban dosa bagi
pelaku, dan hilangnya rasa derita dan dendam korban. Ishlah merupakan perintah
dari Allah yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT,
yang mencintai perdamaian.
d. Tindak Pidana yang dapat dilaksanakan Perdamaian
Kategorisasi tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang dapat
dilakukannya perdamaian adalah qis}a>s. Tindak pidana ini berada di tengah antara
kejahatan hudud dan ta‟zir dalam hal beratnya. Kejahatan terhadap tubuh manusia
sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana
modern sebagai kejahatan terhadap manusia (crimes againts persons) yaitu;
pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai (semi) sengaja, pembunuhan
karena kesalahan dan penganiayaan. Berikut kami uraikan satu-persatu:
1. Pembunuhan Sengaja
Dari beberapa sumber di atas dapat dipahami bahwa terhadap jarimah
pembunuhan sengaja, pelaku dijatuhi pidana qis}a>s yaitu dibunuh kembali.
452 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟I Atas Pelbagai Persoalan Umat,
Bandung: Mizan Cet.XI, 124-127.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
192
Ancaman qis}a>s ini dapat digugurkan atau diganti dengan diat (ganti kerugian)
manakala pihak keluarga korban dan pelaku melakukan perdamaian atau
memberikan maaf. Perdamaian tersebut dimaksudkan sebagai upaya memberikan
kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampunan Allah dan diharapkan di masa
yang akan datang tidak mengulangi perbuatan serupa.
Bahwa unsur-unsur
pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup. Salah satu unsur dari
pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup;
2. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku. Antara perbuatan dan
kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang
terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Pembunuhan dianggap
sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk
membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja.
Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan
sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.453
2. Pembunuhan Menyerupai (Semi) Sengaja
Berbeda halnya dengan pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan
menyerupai (semi) sengaja (qoth’ul syhibhul-‘amd) menurut Hanafiyah seperti
dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembunuhan dimana pelaku sengaja
memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang
mengakibatkan kematian.454
Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan
berbuat berupa perbuatan dan unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat
membunuh. Menurut syafi‟iyah seperti juga dikutip oleh Abdul Qadir Audah,
pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana
pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.455
Pembunuhan
453 Ahmad Wardi Muslich.., 140-141. 454 Abd. Al-Qadir Audah, II.., 93. 455 Ibid.., 94.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
193
menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak
ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak
adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Bahwa
unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja itu ada tiga macam, yaitu:
1. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. Untuk
terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukakn perbuatan
yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan
atau lainnya;
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Adanya kesengajaan
dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan
matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh;
3. Ketiga, kematian adalah akibat perbuatan pelaku. Antara perbuatan pelaku
dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa
kematian yang terjadi merupkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku.456
3. Pembunuhan karena kesalahan (kealpaan)
Pembunuhan karena kesalahan sebagaimana dikemukakan oleh Sayid
Sabiq adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan
untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu
sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan
membunuhnya.457
Sedangkan Wahbah Zuhaili definisi pembunuhan karena
kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik
dalam perbuatannya maupun objeknya.458
Perbuatan yang sengaja dilakukan
sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dariperbuatan
mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
456 Ahmad Wardi Muslich.., 142-143. 457 Sayid Sabiq.., 438. 458 Wahbah Zuhaili, VI.., 223.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
194
Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati
sehingga mengakibatkan bilangnya nyawa orang lain.459
Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu: Pembunuhan
karena kekeliruan semata-mata dan pembunuhan yang disamakan dengan
kekeliruan Pembunuhan karena kekeliruan semata. Dalam kekeliruan yang
pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai
niat untuk mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama
sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang,
tetapi karena kelalaian dan kekurang hati-hatinya, perbuatannya itu
mengakibatkan hilangnya nayawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap
dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena
kelalaiannya.
4. Tindak Pidana Penganiayaan
Tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan adalah setiap perbuatan
menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai
menghilangkan nyawanya.460
Pengertian ini sejalan dengan definisi yang
dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah
setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan
anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan
459 Abdul Qadir Audah mendefinisikan kekeliruan dalam pembunuhan sebagai berikut: Pertama,‟
Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja
melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi
kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Kedua, Pembunuhan yang
dikategorikan kepada kekeliruan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai
maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. Lihat Abd Al-Qadir
Audah II.., 104. 460 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri‟ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-A‟rabi, Beirut,
tanpa tahun.., 204.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
195
hidupnya masih tetap tidak terganggu.461
Bahwa setiap permasalahan pidana tidak
harus berakhir dengan pidana penjara yang sebenarnya pelaku, korban dan
masyarakat telah menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah mufakat
sehingga menghasilkan perdamaian. Hal ini penting mengingat istilah restorative
justice dapat menjadi prospek penyelesaian perkara dalam upaya kebijakan
penanggulangan kejahatan.
2. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia
Restorative justice bukanlah konsep yang baru, keberadaannya barangkali
sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun yang lalu,
upaya penanganan perkara pidana dengan pendekatan ini, justru ditempatkan
sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin
menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan
tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif. Konsep
hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki
konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari restorative justice. Di
Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat
mendukung penerapan restorative justice. Pelanggaran hukum adat merupakan:
1. Suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;
2. Aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;
3. Gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi;
4. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan
keseimbangan kepada keadaan semula.462
Unsur utama dari restorative justice yaitu kerelaan dan partisipasi dari
korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana
461 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 331. 462 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, (Jakarta: CV.
Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 22.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
196
yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat. Pada kenyataan yang ada
dalam masyarakat Indonesia mengenai fungsionalisasi lembaga musyawarah
sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaian perkara pidana.
Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau
dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan, atau dengan melalui
lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu
permasalahan yang muncul. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai
media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi.
Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan
restorative justice, seperti:
a) Victim Offender Mediation (VOM). Mediasi antara pelaku dan korban
yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan
korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator
dalam pertemuan tersebut;
b) Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam
bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya
melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga
korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan
dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku;
c) Circles, suatu model penerapan restorative justice yang pelibatannya
paling luas di bandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum
yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga
anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara
tersebut.463
Ketiga model tersebut, merupakan dasar dari bentuk penerapan pendekatan
restorative justice, yang pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi
variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah
dan mufakat. Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai implementasi dari
nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang
463 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, 170.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
197
kuat. Akan tetapi, penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-
undangan yang jelas. Di bawah ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang
mendukung diwujudkannya pendekatan restoratif hukum pidana Islam di
Indonesia, antara lain:
a. Undang-Undang yang Menggunakan Restorative Justice
Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara
pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri,
termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya
mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu
menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah
hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar
aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di
dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat
dan negara. Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok Thailand dalam Report of
the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
Bangkok, 18-25 April 200, merumuskan bahwa:
“there was general agreement on the need for innovative approaches in
the administration of justice, including the use of alternatives to
imprisonment for minor offences, especially by first time offenders,
juvenile offenders and drug abusers, the use of restorative justice,
including mediation and conciliation, and the need to take into
consideration the rights of victims, in particular those of women and
children.464
Artinya: Terdapat kesepakatan umum tentang perlunya
pendekatan inovatif dalam administrasi peradilan, termasuk penggunaan
alternatif hukuman penjara untuk pelanggaran ringan, terutama oleh
pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan, pelaku remaja dan
penyalahgunaan narkoba. Penggunaan keadilan restoratif, termasuk
464 Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
Bangkok, 18-25 April 2005: The main theme of the Eleventh Congress would be Synergies and
responses: strategic alliances in crime prevention and criminal justice.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
198
mediasi dan konsiliasi, serta pentingnya mempertimbangkan hak-hak
korban, khususnya para perempuan dan anak-anak”.
Begitu juga dalam Kongres PBB ke-12 di Brasil, Report of the Twelfth
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador,
Brazil, 12-19 April 2010, juga merekomendasikan negara anggota untuk
mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya
dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi
penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk
program restorative justice. Dunia internasional telah memberi guidelines on
criminal Justice tentang strategi pendekatan inovasi, komprehensif dan integral
dengan meningkatkan penggunaan program peradilan restoratif.
Dalam kebijakan nasional, ada Pancasila yang merupakan core philosopy
bangsa. Sebagai core philosopy, Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya
sistem hukum di Indonesia.465
Dalam sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung
adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan
yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan,
465 Kuat Puji Prayitno, Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) dalam Pembinaan
Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia, Jurnal Media Hukum, Akreditasi:No.
26/DIKTI/Kep/2005 Vo. 14 No. 3, Yogyakarta, 2007, 152.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
199
sehingga kalau di breakdown falsafah musyawarah mengandung 5 (lima) prinsip
sebagai berikut:
1. Conferencing (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan
keinginan);
2. Search solutions (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang
dihadapi);
3. Reconciliation (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing);
4. Repair (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan
5. Circles (saling menunjang).466
Prinsip-prinsip ini persis seperti yang di butuhkan dan menjadi kata kunci
dalam restorative justice, sehingga secara ketatanegaraan restorative justice
menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.467
Dasar pijakan
itu kalau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung
prinsip yang disebut dengan istilah VOC (Victim Offender Conferencing). Target
dalam pertemuan VOC (Victim Offender Conferencing) adalah mediasi atau VOM
(Victim Offender Mediation), yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling
menyepakati perbaikan.
Umbreit dan Coates menyatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara
dengan VOM adalah to humanize the justice system.468
Pendekatan dikatakan
lebih humanis karena berusaha mengeliminir beberapa masalah;
466 Ibid. 467 Sila kerakyatan ini, bisa disamakan dengan istilah Pinto sebagai Participative democracy in
Restorative Justice di mana korban, pelaku, dan masyarakat berperan penting dalam proses
pengambilan keputusan,. Lihat Pinto, 2005, Is Restorative Justice Possible in Brazil? Dalam
Daniel Achutti, 2011, The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility
to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice, Journal: Oñati Socio
Legal Series, Vol. 1, No. 2, Brazil, 12. 468 Umbreit, Mark and Robert Coates dalam Mara F. Schiff, 1998, Restorative Justice
Interventions for Juvenile Offenders: A Research Agenda for the Next Decade, Online Journal,
Available: http://wcr.sonoma.edu/ v1n1/schiff.html.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
200
1. Tidak lagi mengasingkan hubungan dengan korban pasca proses peradilan
ke tempat sekunder sehingga konsekuensi kejahatan yang dialaminya
seolah tidak diperhatikan. Di sisi lain masuknya para pihak dalam
menyelesaikan masalah adalah significant part dan menjadi ciri khas
model restorative;
2. Secara efektif bertanggung jawab kepada korban atas pemulihan kerugian
material dan moral dan menyediakan berbagai kesempatan untuk dialog,
negosiasi, dan resolusi masalah;
3. Memberi rasa hormat terhadap martabat manusia (the respect for human
dignity), karena peradilan restoratif tidak terpisah dari model perlindungan
hak asasi manusia bahkan mereka berdua mencari kebaikan bersama (they
both seek a common good).
Ada perubahan paradigma mendasar atau redifinisi yang harus dilakukan,
yaitu cara kita memandang kejahatan hakikatnya sebagai masalah kemanusiaan
sehingga tidak melakukan pendekatan formalitas yang berlebihan (excessive
formality) dan hanya mencari kesalahan seseorang, akan tetapi berpikir untuk
memecahkan situasi/masalah, dan harus menyentuh sampai pada konteksnya,
dengan begitu respons kejahatan mestinya mencari solusi problema hubungan
kemanusiaan tadi (care for real people and relationships). Paradigma ini
menggeser anggapan selama ini dari kejahatan sebagai masalah negara menjadi
kejahatan sebagai masalah perorangan, oleh karena itu keadilan yang
diperjuangkan adalah yang mampu menjawab apa yang senyatanya dibutuhkan
korban, pelaku dan masyarakat (experienced within a context). Keadilan yang
demikian dikatakan sebagai“experiencing justice”.
Kaidah musyawarah (sila ke-4 Pancasila) dengan prinsip musyawarah
untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan mengandung esensi
experiencing justice. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh
Jarem Sawatsky pengkaji restorative justice yang bekerja di the Institute for
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
201
Justice and Peace building at Eastern Mennonite University in Virginia sebagai
berikut:
“Needs of victims, offenders and communities are central for Restorative
Justice. Justice is about participation. This has a huge implication for
justice. If needs are central then justice is always ad hoc. Justice must
respond and be experienced within a context. That means justice will look
different and be arrived at differently dependent on the needs, the culture,
the history, the future, and the people involved;469
Artinya: “Korban,
pelaku dan masyarakat butuh keadilan restoratif. Keadilan adalah tentang
partisipasi. Hal ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi
keadilan. Jika kebutuhan merupakan inti, maka keadilan selalu bersifat ad
hoc (tidak tetap/permanen). Artinya; keadilan akan berbeda tergantung
pada kebutuhan, budaya, sejarah, masa depan, dan orang-orang yang
terlibat.
Perbedaan mendasar restorative justice dengan peradilan menurut hukum
acara KUHAP antara lain:
Peradilan KUHAP Peradilan Restoratif
1. Mendasarkan pada kejahatan 1. Menunjuk pada kekeliruan (eror)
Yang dilakukan; yang disebabkan karena pelang-
garan;
2. Menempatkan korban dalam
2
. Menempatkan korban pada posisi
kedudukan yang sentral; yang sekunder
3. Tujuannya berpusat pada gagasan
3. Dasar tujuannya memberi kepuasan
bagaimana menghukum yang ber yang dialami para pihak yg terlibat
salah dengan adil; dalam pelanggaran
4. Retributive Justice
4
. Restorative Justice
469 Jarem Sawatsky, Restorative value: Where Means And Ends Converge, Restorative Justice
Online Journal, Vol. IX, 2010, http://www.restorativejustice.org/arti-clesdb/articles/3681,
Manitoba, Canada, 12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
202
5. Result in prison for the accused;
5
. Dialogue, negotiation,and resolution
6. Ditentukan oleh professional
6
. Ditentukan oleh para pihak dalam
hukum Conferencing
Sejalan dengan itu pula perlu kiranya kebijakan peradilan pidana
Indonesia mengambil langkah-langkah responsif, sinergis dan kombinatif yaitu
selain cara-cara peradilan berdasar KUHAP, ditempuh pula peradilan restorative
justice. Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat
dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut.
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia (UU POLRI), merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam
rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang
melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya
(Pasal 15 ayat (2) huruf k), Berwenang untuk mengadakan tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l);
2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Pasal 8 ayat
(4)) menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan
mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta
wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup
dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat
profesinya;
3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 1 angka (1) adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia. Pasal 50 ayat (1) berbunyi; segala putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili. Serta pasal 5 ayat (1) menyatakan; Hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat;
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
203
4) LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan
perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006) Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (UU LPSK). Ketentuan Pasal 7 UU LPSK menyatakan bahwa
Korban melalui LPSK, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas
restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak
pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh
pengadilan.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan legislasi nasional yang
ada, restorative justice dalam penegakan hukum pidana in concreto dapat
dilakukan dengan berdasar pemikiran sebagai berikut:
1) Melalui kewenangan lembaga LPSK, atau Jaksa dan Hakim di pengadilan,
berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), maupun PP Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi
dan Korban, akan tetapi sejak semula pendekatan yang digunakan adalah
proses restorative justice;
2) Menggunakan kaidah secondary rules yang memberi kewenangan kepada
aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) melakukan creation, extinction,
and alteration of primary rules. Creation, extinction, atau alteration itu
dengan proses restorative justice.
Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang
bagi penegak hukum untuk creation, extinction, atau alteration dalam
menegakkan hukum pidana. Sebagai perbandingan; di Hungaria sejak awal tahun
2007 materi peradilan dengan pendekatan restorative justice sudah efektif.
Restorative justice dengan mediasi tersedia untuk pelanggar baik dewasa dan
remaja jika kejahatannya adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas
atau kejahatan terhadap properti yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun
penjara. Syarat lainnya adalah ada permintaan dari para pihak, tindak pidana itu
ada korbannya, pelaku telah mengaku bersalah, pelaku bukan pelaku yang biasa
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
204
melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau residivis, tidak ada
acara pidana yang tertunda terhadap pelaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan
dan bukan tindak pidana yang menimbulkan kematian.470
Apabila dijumpai keadaan yang demikian itu maka jaksa dan juga hakim
punya keleluasaan (diskresi) untuk menentukan kasus diselesaikan dengan
mediasi/restorasi. Apabila hendak menggunakan diskresinya, mereka
membutuhkan pertimbangan faktor-faktor berikut:
1) Pelaku mengaku selama penyelidikan;
2) Pelaku telah setuju dan dapat memberi ganti rugi kepada korban untuk
kerusakan yang diakibatkan dari tindak pidana itu atau memberikan
bentuk lain dari restitusi;
3) Pelaku dan korban setuju untuk berpartisipasi dalam proses mediasi;
4) Mengingat sifat kejahatan, cara perbuatan tersebut dilakukan dan keadaan
pribadi pelaku sehingga proses pengadilan tidak diperlukan, atau ada
alasan substansial yang dipercaya bahwa pengadilan akan
mempertimbangkan penyesalan pelaku sebagai keadaan yg
meringankan.471
Di Indonesia dengan kewenangan seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “judex mediator”
artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai.
Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut
dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan
nilai yang ada di dalam masyarakat itu.472
470 Borbála Fellegi, Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In
Penal Matters In Hungary, Journal TEMIDA, Mart 2011, 22. 471 Ibid. 472 Kuat Puji Prayitno, Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang
Penegakan Hukum Pidana in concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistim Hukum Nasional),
Disertasi, Undip, Semarang, 2011, 395.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
205
b. Kasus-Kasus yang Bisa Memakai Restorative Justice
Semangat restorative justice dapat terlihat dalam beberapa perundang-
undangan diantaranya: Undang-undang Nomor 15 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 3 1997 tentang Pengadilan Anak,
Undang-undang Nornor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dan Rancangan KUHP 2005. Restorative justice lebih
menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja
sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan
yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka
dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan
menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.473
Melalui pendekatan restorative
justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan
bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat tercapai.
Restorative justice rnerupakan salah satu aIternatif untuk mewujudkan keadilan
sesuai dengan tujuan hukum, Keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik
pelaku, korban maupun masyarakat.474
Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong
terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan
melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan
473 Mudzakkir.., 26. 474 Beberapa teori tentang tujuan hukum: pertama, Teori Etis; keadilan. Kedua, Teori Utilitas:
kebahagiaan. Ketiga, Teori Campuran: ketertiban. Pendapat lain; Mochtar Kusumaatmadja:
tujuan hukum adatah keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut
masyarakat pada zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: tujuan hukum adalah
demi kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan
kctenangan intern pribadi. Lihat Esmi Warassih , Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT
Suryandaru Utruna, Semarang, 2005, 24-25.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
206
kejujuran.475
Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan
masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa
melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas
penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa
berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan
tidak hanya sebatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial,
sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Idealnya, dalam
restorative justice, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula
melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya.
Oleh karena itu perbedaan utama dengan retributive justice terletak pada
filosofinya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melukai
kepentingan masyarakat atau dengan kata lain restorative justice dilakukan
dengan melalui hukum tanpa mencederai perasaan masyarakat.476
Pada saat ini, harapan tersebut bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan
pemerintah (selanjutnya disebut PP) di atas bersinggungan dengan konsep
restorative justice yang dikemukakan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dengan
diaturnya penyelenggaraan pemulihan korban KDRT yang melibatkan kerjasama
dengan berbagai pihak. Menurut PP ini pemulihan korban adalah segala upaya
475 Ibid.., 54. 476 Charles K.B. Barton, Restorative Justice (The Empowerment Model), (Sydney: Hawkins Press,
2003), 38.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
207
untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik
secara fisik maupun psikis.477
c. Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Abdul Qadir Jailani (AQJ).
Kasus pelanggaran lalu lintas tak jarang mengakibatkan kecelakaan.478
Salah satu kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak adalah kasus
pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013
sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Tol Jagorawi KM 08.400 A arah
selatan wilayah Jakarta Timur. Kejadian melibatkan kendaraan Mitsubhisi Lancer
Nopol B-80-SAL, dengan kendaraan Daihatsu Grand Max Nopol B-1347- UZJ,
dengan kendaraan Toyota Avanza Nopol B-1882-UZ. Diketahui bahwa
pengemudi kendaraan Mitsubhisi Lancer adalah Achmad Abdul Qadir Jaelani
berusia 13 tahun, Laki-laki, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Pinang Emas
VII/D4 RT8/3 Pondok Indah Jaksel. Pengemudi kendaraan Mitsubhisi Grand Max
teridentifikasi sebagai Nugroho Brury Laksono berusia 35 tahun, jenis kelamin
laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, dan beralamat di Kampung Bendungan
Melayu Rt 006/01 Rawa Badak Selaran Koja, Jakut. Sedangkan pengemudi
kendaraan Toyota Avanza teridentifikasi sebagai Hendra Sasongko, laki-laki,
pekerjaan swasta, dan beralamat di Asrama Janang Ratmil RT02/02 Jakarta
Utara.479
Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi 8 September tersebut
menewaskan enam orang dan sembilan lainnya luka-luka ini, kecelakaan maut
477 Pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 478 Ferli Hidayat, Analisa Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tersangka Achmad Abdul Qadir
13 tahun. http://ferli1982.wordpress.com/2013/10/16/analisa-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-dengan-tersangka-achmad-abdul-qadir-13thn/ artikel ini diakses pada 13 Oktober 2020.
479 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
208
yang terjadi pada pukul 00:24 dini hari ini menjadikan Abdul Qodir Jaelani atau
yang akrab dipanggil Dul sebagai tersangka utama penyebab kecelakaan tersebut.
Anak bungsu musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobil sedan dengan plat
polisi B 80 SAL ini menabrak pagar pemisah dan masuk ke jalur berlawanan,
yang kemudian mobil yang dikendarainya menghantam mobil Avanza dan
Grandmax yang berisi 13 penumpang yang datang dari arah berlawanan. Peristiwa
yang terjadi di kilometer 8+200 ini terjadi ketika Dul memacu kendaraan dari arah
Cibubur menuju Jakarta. Tiba-tiba saja mobil yang dikemudikan Dul lepas
kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga mobil yang dikendarai Dul melaju
dengan kecepatan di atas 100 Km per jam.480
Lebih jelasnya, kronologis
pelanggaran lalu lintas yang berujung kecelakaan ini terjadi ketika Mobil
Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikendarai oleh Dul datang dari arah selatan
menuju utara menabrak pagar tengah hingga melayang ke arah jalur berlawanan.
Mobil itu menghantam Daihatsu Grandmax B 1347 UZJ dan terdorong mengenai
Avanza B 1882 UZ. Akibat kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 00.45 WIB.
Korban meninggal di TKP sebanyak 6 orang sedangkan 1 orang meninggal di
rumah sakit, jadi korban yang meninggal sebanyak 7 orang, dan 9 orang
mengalami luka-luka.481
Kasus kecelakaan maut ini menjadikan Dul sebagai tersangka, disebabkan
Dul lalai dan mengakibatkan tujuh korban tewas. Selain itu, Dul juga dijerat pasal
berlapis yaitu pasal 310 ayat 3 dan 4 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas,
serta pasal 105 tentang ketertiban, 106 tentang mengemudi dengan wajar dan
480
e-journal.aujy.ac.id/5676/2/KOM104242.pdf artikel ini diakses pada 13 Oktober 2020. 481 Ferli Hidayat, Analisa Kasus Kecelakaan…, diakses pada 13 Oktober 2020.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
209
berkonsentrasi, dan pasal 281 tentang kewajiban pengemudi memiliki SIM.482
Pasal 310 ayat 3 UULAJ No.22 tahun 2009: Setiap orang yang mengemudikan
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),
dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).483
Pasal 310 ayat (4) yaitu: Dalam hal
kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).484
Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Dul mengakibatkan
dirinya harus berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 1 Undang-undang no.11
tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.485
Jika ditinjau dari segi
yuridis, dul masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori
anak anak. Namun dalam undang undang no 11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah
anak yang telah berumur 12 tahun dan di bawah 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana. Perlindungan hukum kepada anak adalah upaya hukum terhadap
berbagai kebebasan dan hak anak (fundamental rights and freedom of children)
482 Ibid.
483 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 484 Ibid. 485
Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
210
serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.486
Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah
mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di
bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan
perlakuan khusus bagi kepentingan psokologi anak.487
Dalam pasal 5 ayat 1 UU No.11 tahun 2012, sistem peradilan anak wajib
mengedepankan pendekatan kedilan restoratif. Untuk mewujudkan keadilan
restorative diperlukan pelibatan seluruh orang-orang yang punya kepentingan dari
suatu tindak pidana yakni pelaku, korban, keluarga korban serta masyarakat.
Untuk memastikan pelaku memikul tanggung jawab pemenuhan kompensasi baik
terhadap korban maupun masyakarat, atas dampak kejahatanya.488
Proses peradilan anak harus bertujuan pada terciptanya Keadilan
Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan
suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban
untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.489
Berdasarkan pasal 6
UU No.11 tahun 2012, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara
korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
486
Muhammad Rajab Ali, Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian‟
Yang Dilakukan Oleh Anak, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2012, 4. 487
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006, 5. 488
Aqsa Alghifarri, Mengawal perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: LBH
Jakarta, 2012, 21. 489
Penjelasan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
211
menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.490
Dalam sistem peradilan anak, skema yang dijalankan adalah setelah
terjadinya tindak pidana, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh
petugas, setelah itu dilakukanya disversi yang melibatkan pihak anak, korban,
keluarga atau wali anak, serta penyidik atas rekomendasi lembaga
kemasyarakatan.491
Kesepakatan disversi dapat berbentuk pengembalian kerugian
dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali
kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau pelayanan masyarakat
paling lama 3 bulan. Namun apabila diversi tidak menyelesaikan perkara, maka
proses peradilan pidana bagi anak dapat dilanjutkan/dilaksanakan dengan Acara
Peradilan Anak di persidanagan. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak
untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis,
psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas)
tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.173
“
490
UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 491 Aqsa Alghifarri, Mengawal.., 46.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
212
BAB IV
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG
RESTORATIVE JUSTICE
A. Sudut Pandang Filsafat Hukum Islam Tentang Restorative Justice dalam
Hukum Pidana Islam
Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang
dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara
maupun lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara
nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun
persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut.
Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadian sangat beragam antara
satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu
didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial
masyarakat yang bersangkutan.
Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil.
Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat
berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang
sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan
mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorativejustice, pelaku harus
bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari
kesalahannya.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
213
1. Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam
Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai
bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu,tidak hanya
sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan
nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative
menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidak adilan sosial
dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal
sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan
sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari
keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan
keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam kontekshukum pidana Islam,
keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hakkorban) dengan tegas
terakomodir dalam diyat ,492
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Al-
Baqarah (2):178-179:493
ى ل ت ق ل ا ف اص ص ق ال م ك ي ل ع ب ت ك وا ن آم ين المذ ا ي ه أ ا ي د ب ع ل وا الر ب الرث والن د ب ع ل ا ى ى ب ث الن ب روف ع م ال ب اع ب ات ف ء ي ش يه خ أ ن م ه ل ي ف ع ن م ف
ان س ح إ ب ه ي ل إ ء ا د ذ وأ ورحة م ربك ن م يف تف ك ى ل د ت اع ن م ذ ف د ع ب ك ليم ل أ اب ذ ع ه ل ف
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar
(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian
492
Ima>m Al-Mawardi>, Al-Ahka>m As-Sult}a>niyyah alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, (Jakarta:
Da>rul Falah, 2007), 365. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, at- Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi:
Muqāranan bi al-Qānun al-Wa’i Jilid I, (Bairut: Dār al- Kātib al-Arabi, t.t.), 204. Ibnu
Qayyim Al-Jauyiyah, Panduan Hukum Islamalih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin’
Sa’adiyatuharamain, cet. ke-2, (Jakarta; Pustaka Azam, 2000), 95. 493
Al-Baqarah (2):178-179.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
214
itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.494
Dan
dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang
yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper
disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama
lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka
membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam
karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan
jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hamba-
hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita
diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum
qisas.495
Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam
terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa
terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang
menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya
seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat,
tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti:
pembunuhan.496
Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap
494
Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang
membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat
(ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik,
umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan
menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si
pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia
mendapat siksa yang pedih. 495
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. Lihat Sayyid Sabiq,
Fikih Sunnah, Jilid 10.., 28. 496
Abdul Qadir Awdah, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah, (Bogor:
Karisma Ilmu, 2007), 204.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
215
perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak
Allah didalamnya (hak masyarakat).497
Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta
merta menjadi hak individul secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam
pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan
diperbolehkan untuk menggantinya dengan ta‟zir. Sehingga, pasca pemaafan yang
diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkanhukuman ta‟zir
kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di
atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented
jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam
tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan
offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks.
Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau
victimoriented. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah,
penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut
ini penjelesannya:
Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan
dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.498
Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat
sejalan dengan qisas-diyat . Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman
model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses
497
Ibid.., 236-237. 498
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni,
1992), 79-84.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
216
peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak
yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya
diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat
digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai
sanksi pidana restitutif. Dalam padangan Muladi dan Barda Nawawi Arief,
keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal.
Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak
prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang
timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada
jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana
dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa
dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-
Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung
beberapa pemikiran:
1. Qis}a>s merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat , atau pemaafan.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum
qis}a>s .
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban
atau wali dan pelaku).
5. Qis}a>s menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Qis}a>s
juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana
pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.499
Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum
alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi
499
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, (Bandung: Al ma‟arif,
1995), 26-29.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
217
antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.
Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana
diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT
dalam surat Al-Hujuraat (49) 9:500
ا م ه ن ي ب وا ح ل ص أ ف وا ل ت ت ق ا ي ن ؤم م ل ا ن م ان ت ف ائ ط ن ى وإ ل ع اها د ح إ ت غ ب ن إ فرى الخ تم ح ي غ ب ت الميت وا ل ات ق ل ف إ يء ف ت للمه ا ر م وا أ ح ل ص أ ف ت اء ف ن إ ف
وا ط س ق وأ ل د ع ال اب م ه ن ي ي ب ط س ق م ال ب ي اللمه نم إ
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.
Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus
berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang
haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.501
Dasar ini kemudian dilihat
dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan
kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa keduanya, memahami baik-
buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian
seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan
dengan pengerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari
pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti
dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang
500
Al-Hujuraat (49): 9. 501
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan, 94.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
218
harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum
pidana modern mempergunakannya.
Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya
mewujudkan legaljustice, tetapi juga mempertimbangkan socialjustice, individual
justice dan juga moraljustice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat
penegak hukum hanya sebatas legal justice. Ini terbukti dengan banyaknya proses
penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan
dimasyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa
yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak
disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang
dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang
seperti diskresi maupun hak opportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana
ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-
nilai moral yang pokok.502
Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu
prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan
individu (al-ada>lah al-fardiyyah) dan keadilan sosial (al-ada>lah al-ijtima>iyah).
Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan
individualitas, bukan hanya sebatas penerapan legal justice.
Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar
bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis
tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak
dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan
kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma dengan
502
Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), 121.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
219
mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.503
Kisah Umar tersebut
menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal justice semata.
Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakatan
dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang
dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga
dengan penerapan diskresi dan diversi.
2. Efektifitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana.
Dalam berbagai wacana aktual, restorative justice atau yang sering di
sebut juga keadilan restoratif merupakan suatu cara khusus untuk menyelesaiakan
kasus pidana diluar pengadilan (Non Litigasi) yang merupakan suata cara khusus
untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun tidak semua
jenis pidana dapat diterapkan dalam sistem ini namun penerapannya bisa
dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan peradilan yang konvensional. Dalam
Restorative justice justru akan lebih less upset about the crime, less apprehensive
and less afraid of revictimization (kurang paham tentang kejahatan, kuruang
memperhatikan dan kurang takut reviktimisasi). Manfaat kedua adalah bagi
komunitass sekitarnya. Restorative justice tidak hanya merestorasi pelaku dan
korban, tetapi juga menyembuhkan pengaruh buruk yang dirasakan komunitas.504
Program perdamaian yang menjadi icon restorative justice diharapkan
akan menjamin keselematan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat
terdampak. Manfaat ketika adalah mengurangi jumlah narapidana dan rsidivis,
503
Umar juga pernah melepaskan budak-budak Hathib yang mencuri unta laki-laki dari Muzainah.
Hal tersebut dilakukan setelah ia mengetahui penyebab perbuatan itu karena mereka kelaparan.
Umar memerintahkan untuk memberikan ganti atas harga unta kepada pemilik unta, bahkan
lebih tinggi dari nominal awal. Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan., 430-431. 504
Sefriani, Jurnal Hukum, Urgensi Rekonseptualiasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Jurnal Media Pembinan Hukum Nasional. Vol.2 Nomor 2. Agustus 2013. 12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
220
dan manfaat keempat adalah menghemat waktu dan biaya.505
Adapun kriteria
yang harus diperhatikan adalah aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis
yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbutan, sifat berbahayanya
perbuatan, jenis pidananya (Strasoort), Berat ringan pidana (Straffmaat), cara
bagaimana pidana dilaksanakan (Strafmodus), dan kondisi-kondisi yange
diakibatkan oleh tindana itu. Sedangkan asepk sosiologis yang perlu diperhatikan
adalah karakter, umur, keadaan si pelaku, latar belakang terjadinya perilaku
tersebut, kondisi kejiwaan pelaku dan apakah pelaku itu pemula atau
bukankemudian pelaku itu memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas
perilakunya, hingga mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada korban,
serta menyesali dan tidak mengulaangi perbuatan yang sama.506
Pada intinya pelaksanaaan restorative justice adalah memperbaiki
kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi
korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku dengan masyarakat.
Keadilan restorasi menawarkan suatu yang berbeda karena mekainisme peradilan
yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog
dan mediasi. Tujuan akhir dan sistem ini adalah membuktikan kesalahan pelaku
dan menjatuhi hukuman diubah menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu
penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Adapun beberapa keuntungan
yang didapatkan dalam penyelesaian menggunakan keadilan restorasi. Pertama,
masyarakat diberikan ruang utnuk menangani sendiri permasalahan hukumannya
yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban Negara berkurang. Secara adminisratif,
jumlah perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga
505
Ibid. 506
Ibnu Artadi, Jurnal Hukum, Dekorstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Jurnal Hukum Pro Justicia Vol 25 No. 1 Januari 2007, 40.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
221
beban institusi pengadilan menjadi berkurang. Dengan begitu maka beban untuk
menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam
hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan pun berkurang.507
Selanjutnya akan
kita jelaskan tentang beberapa pendekatan restoratif dalam hukum pidana Islam
antara lain:
a. Is}la>h Sebagai Mediasi dalam Hukum Pidana Islam.
Mediasi dalam konsep Islam di kenal dengan istilah Is}la>h, beberapa ahli
fiqih memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang
berbeda, yaitu yang mudah dipahami dalam suatu akad dengan maksud untuk
mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang
berakhir dengan perdamaian.508
Dalam termologi fiqih lainnya juga menjelaskan
bahwa mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan Tahkim, yang dalam
istilah tersebut melibatkan dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar
diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar‟i.509
Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang
mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk
menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa
kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau
menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.
Lembaga tahkim telah dikenal sejak sebelum masa Islam. Orang-orang
Nasrani apabila mengalami perselisihan diantara mereka mengajukan perselisihan
507
Yunan Hilmi, jurnal, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan restorative Justive Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Recht Vinding Mediasi Hukum Nasional. Vol. 2 Nomor 2, Agustus 2013, 4.
508 http://www.pa-pekalongan.go.id Mediasi dalam konsep Islam akses 6 september 2020. 509
Samir aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (jakarata: Khalaifa, 2004), 328.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
222
kepada Paus untuk diselesaikan secara damai.510
Allah SWT telah berfirman
kepada kita terkait posisi antara sesama manusia, hal tersebut tercantum
didalam al-Quran surat al-Hujuraat ayat 10 yang artinya:
م ك وي خ أ ي واب ح ل ص أ ف وة خ إ ون ن ؤم م ل اا نم رحون إ ت م لمك ع ل وااللمه ت مق وا
Artinya : “Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara,
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu
itu dan takutlah terhadap Allah“supaya kamu mendaopat rahmat”.511
Ada beberapa bentuk is}la>h dalam Islam yang dikenal antara lain:
1. Is}la>h antara orang Islam dengan orang kafir;
2. Is}la>h antara suami dengan istri;
3. Is}la>h orang yang saling menuntut;
4. Is}la>h dalam hal penganiayaan seperti memaafkan dengan ganti rugi berupa
uang;
5. Is}la>h antara kelompok yang berbuat aniaya dengan orang yang berbuat
adil;
6. Is}la>h untuk memutuskan suatu persengketaan yang terjadi dalam hak
milik.512
b. Ruang Lingkup Is}la> h Dalam Hukum Pidana Islam
Dalam Hukum Islam Ruang Lingkup Mediasi bersumber dalam al-
Mughn>i, Ibnu Quda>mah menjelaskan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh
hakam berlaku segala rupa perkara. Terkecuali dalam bidang nikah, li‟an, qadhaf
dan qisas. Dalam hal ini hanya penguasa yang memberi keputusan. Mediasi
terkandung dalam al-Qur‟an Surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Dalam kandungan
QS. Al Hujurat ayat 9:
ا م ه ن ي ب وا ح ل ص أ ف وا ل ت ت ق ا ي ن ؤم م ل ا ن م ان ت ف ائ ط ن ى وإ ل ع اها د ح إ ت غ ب ن إ فرى االخ ق ف تم ح ي غ ب ت الميت وا ل ل ت إ يء ف ت للمه ا ر م وا أ ح ل ص أ ف ت اء ف ن إ ف
وا ط س ق وأ ل د ع ال اب م ه ن ي ي ب ط س ق م ال ب ي اللمه نم إ 510 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750. 511 QS. Al-Hujurat: 10. 512 http://www.pa-pekalongan.go.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
223
م ك وي خ أ ي واب ح ل ص أ ف وة خ إ ون ن ؤم م ل اا نم ل إ وااللمه ت مق رحونوا ت م لمك ع
”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil.”513
Menurut Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas bahwa suatu
ketika Rasullah mengendarai keledainya menemui Abdullah Ubay. Abdullah bin
Ubay lantas berkata: menjauhlah dari saya karena bau keledai Rasullah ini lebih
wangi darimu.514
Akibatnya pertengkaran antara kedua kelompok tersebut tidak
bisa dihindari sehingga mereka saling pukul dengan menggunakan pelepah kurma,
tangan, dan terompah. Tidak lama berselang turunlah ayat tersebut.515
Sedangkan
dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10:
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah SWT, supaya kamu mendapat rahmat”
Ayat diatas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan
kesatuan, serta hubungan harmonitas antar anggota masyarakat kecil atau besar,
akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan
dan keretakan hubungan mengandung lahirnya pertumpahan darah dan perang
saudara sebagaimana dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah
peperangan.516
Dalam penafsiran lain menjelaskan bahwa orang-orang mukmin
513 QS Al-Hujurat ayat (9 dan 10). 514 Jalaludin As Suyuti, 2008:56 526). 515 HR. Imam Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik. 516
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
224
berorientasi kepada satu dasar dalam persaudaraan, yaitu Iman. Karena itu kalau
mereka bertengkar, damaikanlah saudara seagamamu itu sama seperti kamu
mendamaikan antara saudara keturunanmu.517
Disamping ayat-ayat yang
menunjuk pada kasus mediasi untuk mendamaikan para pihak yang terlibat
sengketa, juga terdapat hadits yang berbicara dalam kasus yang sama, seperti telah
terjadi tahkim dikalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan
tidak ada pula sahabat yang menentangnya.
Contoh ijma>‟ yang melandasi tahki>m adalah peristiwa yang terjadi antara
Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli
kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi
kaki kuda tersebut patah lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda
tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata:
Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah
di antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk
menjadi hakam. Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih
menyatakan kepada Umar: Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan
seperti keadaan semula (tanpa cacat). Maksudnya, Umar harus membayar harga
kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang
membantahnya.518
Umar bin Khattab r.a. dalam pendapatnya juga menjelaskan
sebagai berikut: Kembalikanlah penyelesaian perkara, di antara sanak keluarga
517
Bachtiar Surin, Op,cit. 518
http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/husein_muhammad_alquran.pdf.akses 12 September
2020
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
225
sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya
penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.519
Dalam terminologi Hukum Islam pengertian lain dari mediasi juga bisa
disebut Is}la>h dalam tatanan ilmu fiqih. Yang salah satu akad berupa perjanjian
diantaranya dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan
perselisihan diantaranya keduanya. Dibawah ini adalah terkait dengan rukun Is}la>h
diantaranya:
a). Rukun Is}la>h (perdamaian) adalah:
1) Mus}a>lih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian
untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa;
2) Mushalih „anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau
disengketakan;
3) Mus}a>lih ‘alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihakterhadap
lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan
istilah badal al-s}ulh;
4) Shigat ijab dan Kabul di antara dua pihak yang melakukan akad
perdamaian. Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa
saja yang menunjukan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian,
seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu” „dan pihak lain menjawab‟
“Telah aku terima”.
Adapun rukun Is}la>h (perdamaian) adalah mus}a>lih, Mus}a>lih ’anhu dan
Shighat ijab Kabul antara kedua belah pihak yang melakukan akad
perdamaian. Apabila rukun tersebut telah terpenuhi maka perdamaian diantara
pihak-pihak yang bersengketa telah berlangsung. Dengan sendirinya dari
perjanjian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak untuk
memenuhi/menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian.520
519
Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, terj. Imron AM, dari kitab al-Qada' fi al-Islam, 70.
520 Albulumam Albantani. Hukum Islam, Mediasi dalam penyelesaian perkar, Upload,12 Mei
2010. Akses. September 2020.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
226
b). S}ulhu Terbagi Atas Empat Macam, Yaitu:521
1. Perdamaian antara kaum muslimin dengan masyarakat non muslim, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu
(dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau
dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam Undang-undang yang
disepakati dua belah pihak;
2. Perdamaian antara penguasa (imam) dengan pemberontak, yakni
membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai
keamanan dalam Negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat
dalam pembahasan khusus tentang bugha>t;
3. Perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, yaitu
membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah
durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya
manakala terjadi perselisihan;
4. Perdamaian antara para pihak yang melakukan transaksi
(perdamaian dalam mu’amalat), yaitu membentuk perdamaian dalam
masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi
dalam masalah mu‟amalat.
c). Hikmah dalam Konsep Is}la>h
Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara umat manusia,
Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan
sengketa yang terjadi. Penyelesaian masalah ini dapat melalui Is}la>h
(perdamaian). Imam Ash-Shan‟ani menerangkan hadits diatas dengan berkata:
“Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa
macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami
isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil,
perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim),
perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf
untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk
memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada
harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak.Pembagian inilah yang
dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada
bab ash-shulhu (perdamaian).522
Hikmah Is}la>h dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan
jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada dijalan Allah
521 Pembelajaran Fiqih, http://azizpwd.wordpress.com/2010/05/31/wakalah-dan-shulhu, Akses
September 2020.
522 Imam Ash-Shan‟ani, Subulus SSalam, 4/247.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
227
SWT serta syariat Islam. Serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati
terutama iri dan dengki juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap
lawannya dalam suatu sengketa atau masalah.
c. Prinsip-Prinsip Perdamaian (Is}la>h) dalam Hukum Pidana Islam
Is}la>h dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu
perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses ishlah
antara lain adalah pertama, pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak
yang meliputi pihak yang berkonflik yang dalam hal kejahatan harus ada korban
dan pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang ketiga, ishlah
merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan hak
dan kewajiban.523
Penulis mencoba membaginya sebagai berikut;
a). Pengungkapan Kebenaran
Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang
didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi
kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan fakta yang benar-benar
terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak dapat
ditinggalkan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang merupakan satu rangkaian
dengan masalah konflik dan is}la>h, menyatakan dengan jelas bagaimana
pentingnya suatu kebenaran harus diungkap agar tidak melakukan kedzaliman
kepada kaum lain secara keliru.
لم ا ا ي ه أ ا ي ة ال به ا وم ق وا يب ص ت ن أ وا ن ي م ب ت ف إ ب ن ب ق اس ف م اءك ج ن إ وا ن آم ين ذى ل واع ح ب ص ت يف م اد ن م ت ل ع اف م
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orangfasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
523
Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System &Out
Court System, Jakarta : Gratama Publishing, 2011, 301.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
228
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”
(QS. Al-Hujurat: 6).
Ayat tersebut di atas bukan hanya kewajiban untuk mendapatkan
informasi yang benar, tetapi juga mengandung satu pesan kewaspadaan kepada
para pihak untuk tidak mudah terprovokasi hanya karena informasi yang belum
jelas kebenarannya, sehinga pengungkapan kebenaran sangat penting dan mutlak
dalam menyelesaikan suatu konflik. Is}la>h merupakan satu proses perdamaian
dimana peran informasi yang benar sangat besar, yaitu dijadikan dasar untuk
membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.524
b). Para Pihak dalam Is}la>h
Para pihak dalam ishlah atau perdamaian dapat diketahui dari ayat Al-
Qur‟an sebagai berikut:
ا م ه ن ي ب وا ح ل ص أ ف وا ل ت ت ق ا ي ن ؤم م ل ا ن م ان ت ف ائ ط ن ى وإ ل ع اها د ح إ ت غ ب ن إ فرى الخ تم ح ي غ ب ت الميت وا ل ات ق ل ف إ يء ف ت للمه ا ر م إ أ واف ح ل ص أ ف ت اء ف ن
وا ط س ق وأ ل د ع ال اب م ه ن ي ي ب ط س ق م ال ب ي اللمه نم إ
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai ornag-
orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujurat:9)
Ayat diatas mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk
mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga perintah untuk
melakukan penegakan dari hasil kesepakatan perdamaian, yaitu dengan
524 Ibid, 302.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
229
memerangi pihak yang melanggar kesepakatan damai tersebut. Berdasarkan
pemaknaan tersebut maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah
proses ishlah, yaitu pihak yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau
mushlih (orang yang mendamaikan). Namun, bila melihat konteks surat Al-
Hujurat Ayat 9 yang mengandung perintah kepada pihak ketiga, maka pada
dasarnya mediator sangat penting, bahkan ketika berposisi sebagai pihak ketiga,
menurut ayat tersebut, hukumnya wajib untuk mendamaikan.525
c). Pihak yang Berkonflik
Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak
yang benar-benar memiliki kepentingan di dalamnya, para pihak yang benar-benar
memiliki kepentingan di dalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara
pihak-pihak pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses perdamaian ini
menjadi mutlak adanya. Hal ini dikarenakan ishlah adalah satu proses kesepakatan
antar pihak untuk mendapatkan satu kesepahaman sehinga tidak lagi terjadi
konflik berkepanjangan. Oleh karena itulah, adanya korban dan pelaku adalah
mutlak. Keberadaan pelaku dan korban secara rinci juga ada syarat dan ketentuan
khusus sebagai berikut:
1) Korban, dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung,
yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita
kerugian. Orang yang menderita secara langsung itulah yang memiliki hak
untuk menuntut atau tidak. Ketika kejahatan yang terjadi berupa
pembunuhan, maka korban yang paling dekat yiatu ahli warishlah yag
memiliki hak untuk melakukan Is}la>h. Korban yang dapat melakukan Is}la>h
juga disyaratkan harus dalam keadaan dapat bertanggung jawab dalam
perbuatannya, yaitu bahwa dia sudah dewasa, tidak dalam keadaan gila,
atau dalam keadaan mabuk, atau dalam keadaan tertekan atau terpaksa.526
525
Ibid, 303.
526
Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, 168.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
230
2) Pelaku, dalam Is}la>h harus pelaku yang bertanggung jawab secara pribadi
dalam kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu orang yang jika tidak ada
ishlah maka dialah yang akan mendapat hukuman sesuai ketentuan. Dalam
ishlah tidak diperkenankan ada perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain.
Pelaku sebagai pihak dalam Is}la>h ini adalah orang yang telah jelas sebagai
pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban, yang
berarti pula harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih
dahulu untuk menentukan pelaku yang sebenarnya.
3) Mediator, adalah pihak yang secara independen tanpa memihak kedua
belah pihak membantu penyelesaian sengketa secara aktif. Kebutuhan
akan mediator ditentukan berdasar asas mashlahah.527
Keberadaan hakim
adalah dapat sebagai mediator atau hanya sebatas legitimator hasil
kesepakatan agar pelaksanaan hasil kesepakatan dapat dipaksakan atau
executable.
d). Is}la>h Merupakan Proses Timbal Balik
Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukan
keabsahan dari proses ishlah itu sendiri. Ishlah merupakan kesepakatan dua belah
pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan silah harus dari
kedua belah pihak. Inisiatif dapat muncul dari salah satu pihak dan dapat juga dari
pihak ketiga yang berusaha meng-ishlahkan. Yang jelas, ketika sudah dalam
forum Is}la>h, maka sifatnya sudah suka rela dan tanpa paksaan. Adapun dasar lain
mengenai inisiatif melakukan Is}la>h, yaitu pada ayat sebagai berikut:
ن رد أ ن إ اللمه ب ون ف ل ي وك اء ثمج م يه د ي أ ت م دم ق ا ب ة ب ي ص م م ه ت اب ص أ ا ذ إ ف ي ك افا يق وف وت ا ن ا س ح إ لم ول إ أ م ه ن ع رض ع أ ف وبم ل ق ف ا م للمه ا م ل ع ي ين المذ ك ئ
يغ ل ب ول ق م ه س ف ن أ ف م ل ل وق م ه ظ وع“Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik)
ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri,
kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah:
“Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian
yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-
orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu
berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan
527
Adi Sulityono, Mengembangkan Paradigma NonLitigasi di Indonesia, (Surakarta: UNS Press,
2006), 401.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
231
katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.
(QS. An-Nisa: 62-63).
Berdasarkan pada dua ayat tersebut di atas, jelas bahwa proses perdamaian
dapat diinisiatifkan oleh siapa pun, apakah dari korban, pelaku ataukah pihak
ketiga. Dalam implementasinya, proses ini dapat ditolak oleh salah satu pihak
sehingga ketika sudah menerima proses Is}la>h atau perdamaian ini, benar-benar
merupakan pilihan bebasnya, tidak ada paksaan dan tekanan.
e). Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam
Is}la>h merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak
yangdidalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam surat
Al- Hujurat ayat 9, jelas dinyatakan bahwa ishlah harus diselesaikan atau
dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak
merugikan salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa dalam ishlah konsistensi
keseimbangan para pihak sangat penting eksistensinya. Karena sifatnya konflik,
maka masing-masing memiliki versi kebenaran sehingga Is}la>h akan menyatukan
pandangan mereka dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai tidak
berkepanjangan.
Islam mengingatkan bahwa dalam konteks masyarakat, dalam
menyelesaikan suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat hendaknya dengan
konsep keadilan sosial juga, yaitu dengan meletakkan suatu pada tempatnya,
artinya menggunakan asas proporsionalitas. Memaafkan yang bersalah dan
memberikan bantuan kepada pemalas, disebut sebagai menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan masyarakat, karena hal itu sudah melebihi keadilan sosial itu.528
528
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟I Atas Pelbagai Persoalan Umat,
Bandung: Mizan Cet.XI, 124-127.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
232
Relevansinya dalam pembahasan ini adalah bahwa maaf tidak begitu saja dapat
dijadikan satu metode Is}la>h, harus sangat selektif agar tidak melampaui nilai
keadilan yang itu menggoyahkan sendi kemasyarakatan, dan hanya akan
kontraproduktif terhadap pencapaian perdamaian itu sendiri. Dalam hukum pidana
Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal ishlah, dengan
satu tujuan perdamaian yang sejati, yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku, dan
hilangnya rasa derita dan dendam korban. Is}la>h merupakan perintah dari Allah
yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT, yang
mencintai perdamaian.
3. Konsep Al-‘Afwu ‘(Pemaafan) dalam Hukum Pidana Islam.
Dalam Islam aturan hidup telah ditetapkan melalui sumber hukum yang
mutlak, yaitu Al-Qur‟an sebagai sumber ukum pertama, As-Sunnah sebagai
sumber hukum kedua, ijma ulama (konsensus) sebagai sumber hukum ketiga dan
qiyas (analogi hukum) sebagai hukum keempat. Sumber-sumber hukum Islam tadi
merupakan hirarki dalam sistem Hukum Islam. Undang-undang dan peraturan-
peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari norma-norma
Al-Qur‟an, karena seperti kita ketahui Al-qur‟an itu sebagai batu penguji segala
undang-undang dan peraturan.529
Konsep mediasi pidana dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan
al‟afwu, bahkan ada beberapa ulama yang menyamakan antara Is}la>h dan al‟afwu.
Namun, ketika menyimak pernyataan Shahrour mengenai sinonimitas dalam Al-
Qur‟an, sejatinya tidak ada sinonimitas dalam Al-Qur‟an. Anggapan adanya
529
T.M. Hasby Ash-Shiddiqiey, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang), 119.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
233
sinonimitas dalam Al-Qur‟an akan memberi kemungkinan penggantian firman
Allah dalam Kitab-Nya yang mulia dan anggapan adanya tambahan-tambahan di
dalamnya, di mana pengabaiannya tidak akan merubah atau menambah
kandungan maknanya sedikitpun, dan terhadap hal ini sangat tidak mungkin
terjadi bagi Allah AWT yang maha suci.530
Meski istilah-istilah pemaafan dalam
hukum pidana Islam tidak banyak dirumuskan oleh ulama ahli fiqh, namun tetap
ada penjelasan istilah pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui
batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau tindak
pidana yang dilakukan.
Mengacu pada kajian etimologis di atas maka dapat kita tarik satu
perbedaan secara makna bahasa antara Is}la>h dan al-‟afwu, yaitu bahwa ishlah
adalah proses atau perdamaian itu sendiri, sedangkan al-‟afwu adalah memaafkan,
yang dipersamakan dengan pengampunan. Kata al-„afwu (العف) itu sendiri
merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata al (ال) di depannya, atau
disamakan dengan kata afwun (عف) dalam bentuk masdar nya,yang secara segi
bahasa mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan. Sedangkan kata al-afwu
( افعل ) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama ahli us}u>l Abi> al-
Husain Ahmad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Ra>zi> adalah setiap pembuat dosa
(pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan
sebab telah mendapatkan pengampunan.531
Dalam konteks jina>ya>t dan lebih khusus lagi persoalan pembunuhan,
secara implisit menarik satu garis pembeda antara al-‟afwu dan s{ulh dengan
530
Muhammad Shahrour, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Judul Asli: Nahwu Usul, Jadidah
Li al Fiqih al Islami, cet.I, penerbit ELSAQ Press, 2004. 256-257. 531
Abi> al-Husain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya> al-Ra>zi>, Mujmal al-Lugha>t, (Beirut: Da>r al-
Fikr, 1414 H/1994 M), 472.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
234
melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Jikalau inisiatif pemberian
kompensasi terhadap hukuman qisa>s tersebut berasal dari kedua belah pihak,
maka itu dikatakan Is}la>h (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian
kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka
yang demikian itu masuk dalam kategori al‟afwu (pemaafan).
Pembedaan antara Is}la>h dengan al‟afwu tersebut dapat dikatakan hanya
pada tataran konsep saja, sedangkan dalam praktek, sangat dimungkinkan terjadi
persamaan teknis dalam pelaksanaan antara Is}la>h dan al‟afwu „sebagai satu
metode penyelesaian suatu jarimah. Bahwa Is}la>h merupakan konsep perdamaian
secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan,
dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil
kesepakatan bersama. Sedangkan al‟afwu merupakan satu konsep penyelesaian
perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan
hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat
(kompensasi) atau tanpa kompensasi.532
Dalam hukum pidana Islam berlaku hukum qis}a>s{-diyat , hukuman bagi
pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (qis}>as}) dan ini sesuai rasa keadilan
korban. Tetapi, perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/keluarganya
dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat
(yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa
kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak
itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada
peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana. Is}la>h sendiri dalam
532 Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran.., 290.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
235
Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara
mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses ini antara lain adalah
pertama, pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak yang meliputi pihak
yang berkonflik yang dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku,
sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang ketiga, Is}la>h merupakan proses
sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan hak dan kewajiban.533
Sementara itu, Saamikh As Sayyid Jaad,534
mengungkapkan enam syarat
dalam proses al-Is}lah> wal’afwu ‘anil ‘uqu>bah yang dalam masyarakat umum
dikenal sebagairekonsiliasi. Syarat yang terakhir adalah harus adanya legitimasi
berupa putusan pengadilan agar executable. Dalam konteks penelitian yang
penulis inginkan bahwa, peran dari Al-‘afwu ani al-Uqu>bah ini sebagai salah satu
sarana penyelesaian tindak pidana tertentu yang nantinya dapat diklasifikasi dan
menjadikan dasar legitimasi dalam pembaharuan hukum pidana kedepan.
Penerapan lain dalam konsep pemaafan pidana sebenarnya pidana bisa
juga diterapakan pada kasus jarimah ta‟zir dengan syarat juga yakni berupa
adanya aspek direct victim di dalamnya. Al-afwu „anil „uqubah (pemaafan dalam
pidana) merupakan hal serupa tapi tidak sama dengan konsep Rechtelijk Pardon
(kewenangan jalur pemaafan yang dilakukan oleh hakim), karena kewengannya
pengampunan pidana dalam Al-‘afwu ‘anil ‘uqu>bah ditujukan terhadapa korban
533
Ibid..., 301. 534 Enam Syarat yang diajukan oleh Saamikh Sayyid Jaad, yaitu: 1) pengampunan diberikan oleh
pihak yang memang berhak, 2) pihak yang memberikan pengampunan harus cakap hukum (“aqil
dan baligh), 3) pengampunan tidak boleh atas dasar paksaan, 4) pengampunan harus dengan
kata-kata atau kalimat yang shorih (jelas), 5) pengampunan diikuti pemberian ganti rugi (diyat)
oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, dan 6) pengampunan harus dilegitimasi oleh
putusan pengadilan agar executable. Lihat dalam M. Abdul Kholiq, Impunitas Kejahatan
MasaSilam (Sebuah telaah Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam), Pointer diskusi
disampaikan pada forum diskusi Bedah Buku Berjudul Menolak Impunitas, diselenggarakan oleh
LEM FH UII, pada tanggal 27 Februari 2006, hal 5. Sebagaimana dikutip dalam Mahrus Ali,
Syarif Nurhidayat.., 307.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
236
jarimah, sedangkan dalam konsep Rechtelijk Pardon ada pada seorang Hakim. Al-
afwu anil uqubah jika diperbandingkan dengan konsep hukum pidana barat
sebenarnya cenderung bersinergi terhadapa konsep Islam tentang rekonsiliasi,
sebagai suatu media penyelesaian kejahatan yang bersifat Out Cort System, tetapi
tetap dalam koridor/kerangka hukum.535
Jika kita telaah dalam Filosofi konsep Al-„afwu„ an al-uqu>bah,
penjatuhan dan pelaksanaan pidan sesungguhnya hanya merupakan salah satu
media atau cara untuk menyelesaikan berbagai problem kejahatan dengan
berbagai macam orientasi tujuan (tujuan penjatuhan pidana). Secara konseptual
tujuan dari hukum pidana Islam adalah:
1. Dar’ul mafa>sid wa jalbu al mas}a>lih sebagai tujuan umum;
2. Sedangkan tujuan khususnya ialah berupa:
Arrodu wa al-jaza> (pembalasan dan pencegahan kejahatan);
At-ta’di >bu wa al-Isla>hu (pengajaran/pembinaan dan kebaikan
hidup bersama.
Karena dalam proses perbaikan diri pelaku kejahatan yang tumbuh secara
internal menjadi penekanan utama dalam pemidanaan Islam, maka dalam
pemidanaan Islam tidak ada pola pidana yang limitatif atau berpola antara, seperti
yang terdapat dalam KUHP atau UU pidana lainya di luar KUHP.536
Orientasi
tujuan al-Is}la>h}u (perbaikan diri) mengandung makna bahwa dengan hukuman itu
Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang baik yang dilandasi rasa saling
menghormati dan mencintai di antara sesama anggota masyarakat, namun dengan
tetap menyadari batas-batas hak dan kewajiban.
535
Muhammad Abdul Kholiq AF, Kumpulan Materi Sistem Pemidanaan Islam Pemaafan pidana. Fak. Hukum. Universitas Islam Indonesia, 1.
536 Ibid.., 4.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
237
Upaya perwujudaan dalam tujuan-tujuan pidana Arrodu wal jaza dan
Atta’di >bu wal Is}lahu adalah bersifat utuh (integral) bahwa pidana Islam tidak
mesti harus berat atau ringan, tetapi yang penting predictable dapat mewujudkan
tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan:
1. Roddu al-mafsadah bi al-‘uqu>bah (mencegah kerusakan dengan hukuman)
2. Wuju>du al-ada>lah bil‘uqu >bah (adanya suatu keadilan dengan hukuman)
3. Wuju>dullmas}lahah bil’uqu >bah (mewujudkan kemaslahatan dengan
hukuman)
Secara kontekstual dalam firman-Nya, Allah Swt telah memaafkan
banyak kedurhakaan dan kesalahan hamba-hambanya. Dalam penggalan arti
surat Asy-Syura (42) ayat 30, Artinya:
ي ث ك ن وع ف ع وي م يك د ي أ ت ب س ك ا م ب ف ة ب ي ص م ن م م ك اب ص اأ وم
“Dan apa yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan
tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan banyak.”
Seandainya Allah Swt tidak memaafkan mereka, tentu semuanya akan
binasa bahkan tidak akan ada lagi satu binatang melatapun di dunia ini.537
Oleh
karena itulah Allah Swt memberi gelar diri-Nya al-Afwu, Yang Maha Pemaaf.
Allah Swt berfirman, Artinya:
JIka kamu menyatakan sesuatu kebaikan menyembunyikan atau
memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah
Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. (QS An-Nisa (4) ayat 14. Dan; Artinya:
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (QS Al-A‟râf (7):199)
Memaafkan kesalahan dan kezhaliman orang lain kepada kita tidaklah
mudah. Menurut para sufi, memaafkan harus dilatih secara continue dan terus-
537
Ibid.., 169.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
238
menerus. Sifat pemaaf tumbuh karena kedewasaan ruhaniyah. Ia merupakan hasil
perjuangan berat ketika kita mengendalikan kekuatan ghadhab (marah) di antara
dua tekanan yaitu pengecut dan pemberang.Memaafkan juga tidak bisa direkayasa
secara artifisial dengan upacara pemutihan seperti halal bi halal dan lain
sebagainya. Maaf yang tulus lahir dari perkataan yang tulus kepada orang lain.538
Ketika Misthah bin Utsa>tsah (anak bibinya Abu Bakar yang hidupnya miskin dan
tidak punya harta benda) dibantu dan dinafkahi oleh Abu Bakar, namun Misthah
malah menyebarluaskan isu negatif terhadap Âisyah (isteri Nabi Saw dan putri
Abu Bakar,539
yang kemudian sang ayah tidak membantu dan menafkahi lagi.
Kemudian Allah SWT menegurnya dengan ayat:
“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan
di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan)
kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang
yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan
berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?
dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nûr
(24): 22)
Karena itu, mereka yang enggan memberi maaf, pada hakikatnya
berarti enggan memperoleh pengampunan dari Allah Swt. Dalam pandangan
Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain termasuk sebagian dari akhlak
yang sangat mulia dan luhur.540
Ia merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa
538
Jalaluddin Rahmat, Reformasi Sufistik, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002, 218. 539
Kisah tersebut terjadi dalam hadîtsul ifki (berita bohong), di mana ketika kaum muslimin
melakukan perjalanan pulang dari perang Bani Musthaliq kemudian tersebar berita bohong
bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan keji dengan Shafwan bin Mu‟aththal. Yang pertama
kali menyebarkan berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian Masthah ikut
andil menyebarluaskan berita tersebut. Allah Swt lalu menurunkan surat An- Nur (24); 221
sebagai pembelaan kepada Aisyah dan untuk meyakinkan Rasulullah Saw bahwa berita itu
hanyalah fitnah dan kabar bohong semata. Dalam Muhammad Sa‟îd Ramadhân al-Bûthy, Sirah
Nabawiyah, (Jakarta: Rabbani Press, 1428 H/2007 M), 291-294. 540
Rasulullah Saw sudah sering mencontohkan sikap mulia tersebut, sehingga beliau Saw sangat
terkenal sebagai orang yang pemaaf. Dalam sejarah disebutkan bahwa beliau Saw taburkan
maafnya kepada orang-orang yang menyakiti dan yang mengusirnya dari tanah airnya. Bahkan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
239
(muttaqi>n) dan ia adalah sikap yang diutamakan di sisi Allah Swt. Kemudian
dalam hadist yang diriwatkan oleh Imam Ahad bin Hanbal. Rasullah SAW telah
menegaskan akan hal tesebut ketika sahabat Uqbah bin Amir541
bertanya
mengenai amalan-amalan yang paling utama. Beliau menyambutnya dengan
bersabda:
“Dari Uqbah bin Amir ia berkata; saya bertemu dengan Rasullah SAW
kemudian saya pegang tangannya dan bertanya; Wahai Rasullah
beritahulah saya yang amalan-amalannya yang paling utama; Beliau
SAW kemudian menjawab. Wahai Uqbah sambunglah tali persaudaraan
dengan orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, berilah
orang yang tidak mau memberi kepadamu dan maafkanlah orang yang
telah mendzalimimu”.
Oleh karena itu, jika ada seseorang yang berbuat zhalim kepada kita, yang
diutamakan dan diperintahkan oleh agama adalah memaafkan kesalahan atau
kezahaliman orang tesebut, walaupun membalas kezhaliman atau keburukan juga
diperbolehkan, namun memaafkan tetap lebih utama. Hal ini tampak jelas dalam
firman Allah SWT;
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka
barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang
zhalim.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 40).
Namun, kalau kita melihat realita kehidupan sehari-hari, yang terjadi justru
sebaliknya. Pemaafan itu biasanya muncul dan terjadi setelah orang yang berbuat
salah atau zhalim meminta maaf terlebih dahulu. Padahal, kalau kita meneliti dan
mengkaji ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan masalah maaf memaafkan
(al-„Afwu), akan kita temukan bahwa konsep Al-Qur‟an mengenai al-„Afwu
adalah perintah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah atau zhalim
beliau Saw serahkan sorbannya sebagai tanda maafnya kepada Wahsyi yang telah membunuh
pamannya tercinta Hamzah. Dalam Jalaluddin Rahmat…, 218. 541 Ahmad ibnu Hanbal, Musnad Ahmad, (Beirut: Darul Fikr, T.th), hadits Uqbah ibn Âmir, juz 35,
206.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
240
bukan perintah meminta maaf, sehingga kita perlu menanti permohonan maaf dari
orang yang bersalah, tetapi hendaknya sebelum diminta.
Relevansinya dalam pembahasan ini adalah bahwa maaf tidak begitu saja
dapat dijadikan satu metode mediasi pidana, harus sangat selektif agar tidak
melampaui nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan hanya akan
kontraproduktif terhadap pencapaian perdamaian itu sendiri. Hukum pidana Islam
memberikan solusi untuk dua arah, yang seimbang melalui ishlah, dengan tujuan
perdamaian yang sejati, yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku, dan hilangnya
rasa derita dan dendam korban. Al-„afwu„merupakan perintah dari Allah yang
harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT, yang mencintai
perdamaian.
4. Pembaruan Hukum Pidana Islam dalam Pembangunan Hukum Pidana
Nasional.
Gerakan pembaruan hukum Islam, termasuk hukum publik Islam tidak
dapat dilepaskan dari aspek dan pengaruh pluralitas sosial-budaya, politik dalam
suatu masyarakat dan negara. Para ulamā/fuqāhā seringkali menafsirkan teks-teks
Alqur‟an dan Sunnah dalam konteks sosial-budaya dan politik.542
Fakta sejarah
menunjukkan pada masa Islam yang begitu awal, telah lahir berbagai madzhab
fiqh, ada madzhab Hijaz, madzhab Irak dan Syiria.543
Kendati demikian, rumusan
teori hukum Islam baru ditemukan pada abad ke-2 H.Tercetus oleh seorang
542 A. Qodri A. Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum
Umum,(Yogyakarta: Gama Media, 2002), 32-33. 543 Abdꞌ al-Wahha>b Ibra>hi>m Abi> Sulaima>n, al-Fikru al-Us}u>li>; Dira>sah Tahli>liyyah Naqdiyyah,
(Jeddah: Da>r al-Syuru>q, 1983), Cet. ke-1, 44-46.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
241
bernama al-Syafi‟i melalui karyanya al-Risālah.544
Selanjutnya, gagasan
pembaruan hukum Islamditeruskan oleh al-Ghazali (w.505/1111) dengan
membangun teori mashlahah, dan kemudian dilanjutkan oleh al-Syāthibi>
(790/1138). Dan, pada awal fase modern muncul Muhammad Abduh (w.1905)
dengan rekonstruksi rasionalisme klasik.545
Secara umum, pola pembaruan hukum Islam, telah terbagi menjadi dua
kelompok:
1. Kelompok ahli hukum Islam (fuqāhā/mujtahid) yang dikategorikan
dengan aliran “tekstual-teosentris”. Kelompok ini selalu menjadikan teks-
teks Alquran dan Sunnah sebagai pijakan utama dalam justifikasi aktivitas
mereka. Artinya, teks-teks yang jelas dan rinci dalam bidang hukum Islam
yang terdapat dalam Alquran dan sunnah dan kitab-kitab karya ahli fiqh
tradisional harus diterima apa adanya tanpa membutuhkan tafsir ulang.546
2. Kelompok ahli hukum yang diidentikkan dengan orang “legal theory”.
Yakni kelompok yang berpandangan bahwa agar hukum Islam selalu
mampu menjawab tantangan zaman dan tak kehilangan peran vitalnya,
maka pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Mereka ini kelompok
yang mengedepankan peran akal dan memberikan porsi utama dalam
menjawab realitas dan perubahan sosial.547
Pada perjalanan sejarah berikutnya, pembaruan hukum Islam selalu
diwarnai perdebatan antara peran wahyu versus akal (teks versus konteks).
Pertentangan antara Umar dan Sahabat lainnya terkait pembagian ghani>mah ,548
544 Terkait siapa sejatinya penemu ilmu ushul al-fiqh masih menjadi perdebatan. Secara praktis
praktik-praktik hukum berbasis pembaruan telah ada sebelum Asy-Syafi‟i. Tidak mengherankan
jika dari kalangan Ahnaf, mengklaim bahwa Abu Hanifah, Syaibani dan Abu Yusuf adalah
tokoh-tokoh peletak ilmu ushul al-fiqh. Dapat dikatakan pada era mereka memang telah
terbentukmetodologi hukum Islam, namun masih membaur dengan kajian-kajian lainnya,
semisal fiqh dan sebagainya. Baru pada era al-Syafi‟i, beliaulah yang menyusun ilmu Ushul al-
Fiqh secara sistematis dan terpisah dari ilmu-ilmu lainnya. Detailnya lihat karya Abd al-Wahhab
Ibrahim Abi Sulaiman.., 5-6. 545 Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Ainurrofiq (ed.),
Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press
dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 148-149. 546 Satria Effendi M, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memposisikan KH Ali Yafie dalam
Jamal D. Rahman (ed.) Wacana Baru FiqhSosial; 70 Tahun KH Ali Yafie„(Bandung: Mizan,
1997), 154-155. 547 Ibid.., 154. 548
Ghani>mah adalah harta yang diambil secara paksa dari golongan kafir harbi, baik dalam
bentuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak,baik diambil ketika pada saat
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
242
terkait pemotongan tangan bagi pencuri, pertentangan antara Abu Hanifah dengan
teori istihsān-nya dengan penentangnya Asy-Syafi‟i dengan teori qiyās-nya. Ini
semua membuktikan kepada kita bahwa perdebatan wahyu versus akal, teks
versus konteks, selalu menghiasi sejarah pembaruan hukum Islam, termasuk
upaya-upaya reaktualisasi hukum pidana Islam (HPI). Gelombang pembaruan
hukum pidana Islam (HPI) sejatinya tidak bisa dilepaskan dari metodologi
(epistemologi) yang digunakan para pembaru tersebut. Harus diakui, antara
epistemologi yang dipakai dengan produk ilmu yang dihasilkan mempunyai
keterkaitan yang erat dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Artinya, corak hukum
dari seorang mujtahid sangat dipengaruhi metode (episteme) yang dipakai oleh
mujtahid itu sendiri. Keduanya, antara hasil hukum dengan epistemologi
(metodologi) ibarat matahari dengan sinarnya yang tidak bisa dipisahkan.
Membedah tentang aspek epistemologi, maka tidak bisa lepas dari kajian
filsafat. Dan, bagian filsafat yang dengan sengaja berusaha menjalankan refleksi
atas pengetahuan manusia itu disebut epistemologi atau ajaran tentang
pengetahuan. Karenanya, Amin Abdullah memandang bahwa epistemologi
merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang memperbincangkan
pengetahuan. Sebagaimana diketahui, bahwa perbincangan epistemologi tidak
dapat meninggalkan persoalan-persoalan yang terkait dengan sumber ilmu
pengetahuan dan beberapa teori tentang kebenaran. Sedangkan menurut
Komaruddin Hidayat epistemologi dimaknai sebagai teori dan sistem tindakan
dan cara pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya.549
peperangan masih berlangsung ataupun ketika memburu musuh yang melarikan diri. Sedangkan
fa‟I adalah harta yang diambil secara paksa tanpa melalui peperangan, sementara salab ialah
harta atau senjata pribadi yang ada pada mayat tentara musuh yang terbunuh. 549 Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, (Jakarta: Paramadina, 1996), 56-7.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
243
Sementara Harun Nasution mengatakan bahwa epistemologi merupakan
ilmu yang membahas tentang dua ranah yaitu: apa itu pengetahuan, (hakikat) dan
bagaimana cara memperoleh pengetahuan.550
Sedangkan Harold H. Titus
mengatakan bahwa kajian dalam epistemologi terdapat tiga persoalan yang selalu
diperbincangkan. Pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari
manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana mengetahui? Hal ini
adalah persoalan tentang “asal” pengetahuan sendiri. Kedua, apakah watak
pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar akal-pikiran, dan
kalau ada apakah kita mengetahuinya? Hal ini adalah persoalan tentang, apa yang
kelihatan versus hakekatnya pengetahuan. Ketiga, apakah pengetahuan itu benar
(valid)? Bagaimana dapat membedakan antara benar dan salah dalam
pengetahuan? Hal ini adalah persoalan tentang kebenaran atau verifikasi
pengetahuan yang telah diperoleh manusia.551
Terkait dengan problema-problema dalam epistemologi fiqh al-jina>yah itu
sendiri, dalam hal ini Mohammed Arkoun menegaskan bahwa dalam khazanah
keilmuan ke-Islaman tradisional, yang dimaksud dengan epistemologi dalam
hukum pidana Islam adalah disiplin ilmu us}u>l al-fiqh atau yang dikenal dengan
teori hukum Islam. Us}u>l al-fiqh merupakan metodologi terpenting yang
ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki umat lainnya.552
550 Harun Nasution, Filsafat Islam, (Jakarta: UI-Press, 2001), Cet ke-16, 10. Lihat juga dalam
karyanya yang berjudul Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI-Press, 1990). 551 Harold H. Titus, dkk. Persoalan-persoalan Filsafat, terj. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang,
1984), 186-188. 552 Dalam pandangan Arkoun, ilmu (kajian) Ushul al-Fiqh terutama kaitannya dengan kajian
hukum Islam, maka sejatinya Ushul al-Fiqh merepresentasikan kajian epistemologi tersendiri
dalam hukum Islam. Perkembangan dan corak, karakteristik hukum Islam (fiqh) sangat
ditentukan oleh Ushul al-Fiqh itu sendiri. Lihat dalam Muhammed Arkoun, The Concept of
Authority in Islamic Thought dalam Mehdi Mozaffari and Ferdinand (ed.). Islam: State and
Society, (London Curzon-Press, 1988), 62.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
244
Kedudukan us}ūl al-fiqh sebagai epistemologi hukum pidana Islam
(jinayah) bersifat mutlak. Sebab disiplin inilah yang mempunyai kaidah-kaidah
dasar yang harus diperhatikan dalam merumuskan hukum pidana Islam. Selain itu,
us}ūl al-fiqh juga dinilai sebagai metodologi penetapan (itsbāt) sebuahhukum.
Sebagai sebuah epistemologi, ushūl al- fiqh sudah layak dan memadai. Alasannya
pada pertimbangan bahwa us}ūl al-fiqhdi dalamnya memuat kriteria-kriteria yang
dibutuhkanbagi sebuah epistemologi: hakikat (realitas), sumber dan metode serta
validitas (ukuran sebuah kebenaran) yang kesemuanya telah teruji dalam
pembentukan hukum Islam dari waktu ke waktu. Dalam beberapa literatur juga
disepakati bahwa us}ūl al-fiqh sangat identik dengan metodologi hukum Islam.
Proses perjalanan sejarah perumusan dan pembaruan metodologi hukum
Islam (ushūl al-fiqh), paling tidak dijumpai tiga karya besar yang dipandang
merepresentasikan zamannya dan karakteristiknya masing-masing. Pertama,
adalah karya besar al-Syafi‟i yang bernama al-Risālah. Kedua, adalah karya al-
Syathibi dengan al-Muwāfaqāt-nya, dan ketiga adalah karya Sharur yang berjudul
al-Kitāb wa al-Qur‟a>n dan Nahw Us}ūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī.
Karakteristik yang ada us}ūl al-fiqh karya al-Syafi‟i adalah teologis-deduktif yang
terpaku pada literalisme teks. Corak semacam ini kemudian diikuti oleh para
teoritisi dari kalangan mutakallimūn baik dari Syaf‟iyyah, Malikiyyah maupun
Hanabilah. Sedangkan dari teoritisi Hanafiyah mempunyai corak yang berbeda
dengan menekankan pendekatan induktif-analitis. Kendati demikian, karya-karya
us}ūl al-fiqh dari kalangan Syafi‟iyyah dan Hanafiyyah mempunyai kesamaan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
245
yaitu sama-sama menekankan paradigma tekstualisme (literalisme).553
Paradigma
tekstual ini berjalan selama berabad-abad kurang lebih lima abad, yaitu dari abad
ke-2 H sampai abad ke-7 H.
Perjalanan sejarah pembaruan us}ūl al-fiqh berikutnya adalah pada awal
abad ke-8 H/14 M. Ini ditandai dengan munculnya paradigma baru dalam us}ūl al-
fiqh yang diusung oleh al-Sya>thibi> (w.790/1388) melalui karya monumental yang
berjudul al-Muwāfaqāt fi Us}ūli al-Syarī‟ah. Melalui karyanya ini al-Syathibi telah
menawarkan teori baru yang mengacu pada maksud Allah yang paling utama
dalam perumusan hukum. Sebuah revolusi teori yang lebih menekankan
pendekatan maqās}idy dari pada pendekatan kebahasaan (lughawi) yang selama ini
banyak digunakan para teoritisi sebelumnya.554
Selepas era al-Syathibi, kajian
us}ūl al-fiqh mengalami stagnasi luar biasa. Ini ditandai dengan kemandegan
kajian dan dinamika metode studi Islam. Gagasan al-Syathibi lahir pada masa
umat Islam larut dalam keterpakuan teks yang kuat. Sehingga, ide-ide cemerlang
yang diretas oleh al-Syathibi pada masanya kurang mendapatkan respon dari umat
Islam saat itu.555
Kendati demikian, apresiasi patut dilayangkan buat al-Syathibi
yang telah merumuskan teori baru di tengah era keterpakuan teks.
Lima abad kemudian, di era modern telah bermunculan para pembaru
ushūl al-fiqh. Sebut saja nama Muhammad Abduh (w. 1905) dengan karyanya
yang telah diedit oleh Dr. Ima>rah yang berjudul al-A‟māl al-Kāmilah li al-Imām
Muhammad Abduh. Berikutnya adalah Rasyid Ridla (w. 1935) dengan karyanya
553 Muhyar Fanani, Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 163-164. 554 Louay Safi, Ancangan Metodologi Alternatif (The Fondation of Knowledge; A Comparative
Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2001), 143. 555 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra‟ al-Ma‟nawi
al-Syathibi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 186-188.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
246
yang berjudul Yusral-Islām wa Us}ūl al-Tasyrī‟ al-Ām, disusul oleh
pembaruberikutnya yaitu Abd al-Wahha>b Khalla>f (w. 1956) dengan karyanya
yang berjudul Mas}a>dir al-Tasyri‟ fi> ma Lā Nas}s}a fī >hi dan Hasan al-Turabi dari
Sudan dengan karyanya Tajdīd Us}ūl al-Fiqh. Ada juga nama al-Fasi (w.1973).
Namun demikian, para teoritisi tersebut dalam pandangan Hallaq, belum
merumuskan teori baru, melainkan hanya melakukan revitalisasi teori mashlahah
yang diretas oleh al-Syathibi. Oleh karena itu, Wael B. Hallaq menyebut bahwa
para teoritisi tersebut termasuk dalam kelompok pembaru penganut aliran
utilitarianisme.556
Di Indonesia sendiri, corak dan karakteristik hukum Islam yang ada
termasuk entitas al-fiqh al-jina>’i> disinyalir masih banyak diwarnai pemikiran
bernuansa Arab dan Timur Tengah yang sejatinya dalam beberapa hal tidak lagi
relevan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga
dalam hukum adat. Akibatnya, menurut sebagian ahli, ada bagian-bagian tetentu
dari hukum Islam yang kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat
Indonesia. Bentuk-bentuk hukuman pidana tersebut, menurut Munawwir Sjadzali,
adalah hukuman bernuansa Arab.557
Realitas-realitas empiris di atas pada gilirannya kemudian mendorong
perlu dilakukannnya rekonstruksi epistemologi-metodologi untuk mewujudkan
fiqh (hukum Islam) bercirikan ke-Indonesiaan. Ide dan gagasan ini banyak
diusung oleh pembaru-pembaru Indonesia seperti Hasbi Ash-Shiddieqy dengan
fikih Indonesia, Hazairin dengan fikih madzhab nasional, Ibrahim Hossein dengan
556
Wael B. Hallaq.., 318-333. 557
Munawwir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), 4-26. Baca juga buku
karya Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr.
Munawwir Sjadzali, MA, (Jakarta:Paramadina, 1995).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
247
teori zawājir, Ali Yafie dan Sahal Mahfudh dengan fikih sosial dan Abdurrahman
Wahid dengan pribumisasi Islam, Nurcholis Madjid dengan sekularisasi Islam dan
lain-lainya.558
B. Konstruksi Pendekatan Restorative Justice Hukum Pidana Islam dalam
Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Perkembangan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hukum sebagai
pranata kehidupan bermasyarakat memberikan pengaruh yang sangat kuat
terhadap perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia. Fenomena
menunjukkan munculnya berbagai kontroversi terhadap proses dan putusan sistem
peradilan pidana yang dianggap oleh sebagian pihak tidak memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Munculnya Konsep restorative justice yang dianggap
sebagai gagasan baru dalam sistem hukum pidana, pada dasarnya memiliki
metode dengan pola tradisional penyelesaian konflik dan kejatahan yang telah
hadir di berbagai kebudayaan sepanjang sejarah manusia. Sistem hukum pidana di
Indonesia memberikan ruang untuk diterapkannya konsep restorative justice, yang
secara substansial juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam.
Oleh karena itu, konsep restorative justice dianggap sebagai konsep yang tepat
dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan lebih efektif untuk dapat
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, akan penulis uraikan beberapa
pendekatan dalam pembaruan hukum pidana nasional:
1. Ijtihad Umar bin Khattab
558
Ibnu Burdah (ed.) dalam Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum
Islam dan Islamisasi Hukum Nasional pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008),
114.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
248
Ijtihad Umar bin Khattab, yang secara peristiwa terkesan mengalami
evolusi dari teks kepada konteks, dalam waktu yang berbeda, adalah lebih kepada
mempertimbangkan etika dasar kesadaran moral Islam-nya. Jadi, tidak semata-
mata selesai jika hanya dilihat dari teks dan konteks penerapan nas-nas.
Melainkan juga penting dilihat kebutuhan penerapan kesadaran nilai-nilai etika.
Dengan adanya ijtihad Umar, dan dari sudut paradigma lainnya, dapat dinyatakan
bahwa pemikiran Umar, lebih mengedepankan relativisme etika keyakinan moral
berbasis Islam. Sehingga, ada pertimbangan moral yang menghendaki putusan,
yang jauh lebih baik dari putusan moral lainnya, pada waktu itu. Umar bin
Khattab (Umar), sosok yang luar biasa. Kepintaran, gagasan dan ijtihadnya lebih
sering mendapatkan legitimasi dari wahyu. Namun, di masa-masa pasca wafatnya
Nabi Muhammad Saw, yaitu pada masa kekhalifahannya, gagasan ijtihad Umar
bin Khattab memperlihatkan arah yang oleh sebagian ulama dipandang sebagai
progresif, bahkan terkesan berbeda dengan teks Al-Qur‟an dan Hadis,559
sekalipun
hanya pada beberapa musim atau konteks dan kondisi tertentu.
Putusan ijtihad Umar bin Khattab ini, sering disampaikan secara tegas.
Ketegasannya ini cenderung diwarnai oleh karakternya sendiri.560
Dalam beberapa
kasus karakter dalam memberikan ijtihad ataupun putusan justru menguntungkan
bagi kemajuan Islam. Selain umat Islam telah banyak dianut oleh wilayah-wilayah
sekitar jazirah Arab, dan bahkan lebih jauh dari itu sampai ke Spanyol, dan
masalah-masalah sosial kemasyarakatan juga sudah sangat banyak, yang berbeda
dengan masalah pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, maka ketegasan
559 M.H. Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (A. Audah, Trans.), (Jakarta, Litera Antar Nusa:
1998), 111. 560 Azumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta, Intermasa: 1996), 13.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
249
putusan seorang Umar bin Khattab, sangat diperlukan saat itu. Umar bin Khattab
adalah sosok yang sudah banyak mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi
Muhammad Saw. Sehingga, sebagaimana Nabi Muhammad Saw mengajarkan
umatnya dalam bermusyawarah dan berpendapat ketika itu, terkait dengan
masalah-masalah yang ada, tak dapat dipungkiri semua itu menjadi modal bagi
seorang Umar bin Khattab untuk terus berusaha memberikan putusan-putusan
dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap kasus atau masalah yang ada,
terutama pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw.
Pertimbangan, argumentasi dan solusi-solusi atas masalah yang ada, dalam
perkembangan selanjutnya disebut ijtihad, yang sampai sekarang dikenal dengan
pengetahuan atau kajian fikih dan ushul fikih. Bahkan Umat Islam sangat kental
sekali nuansa kajian fikih, ushul fikihnya. Sehingga tidak heran ada beberapa ahli
yang mengatakan bahwa, jika Yunani pada masanya pernah dikenal memiliki
sejarah dan peradaban filsafat, maka umat Islam bisa dikatakan memiliki sejarah
dan peradaban fikihnya, yang sama sekali tidak dapat dihubung-hubungkan
dengan sejarah dan peradaban lainnya. Artinya kajian pengetahuan fikih, murni
muncul dari umat Islam itu sendiri. Dan yang mencoba-coba menghubungkannya
dengan peradaban lainnya seperti Yunani atau hukum Romawi, adalah hal yang
sia-sia.561
Dalam hal ini objek kajian fikih yang terkait dengan putusan Umar hanya
melihat pada beberapa kasus saja yaitu hukum potong tangan, ghani>mah , talak,
561
Nirwan Syafrin, Konstruk Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh.
TSAQAFAH, 5(2), (2009).., 227.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
250
mualaf, pezina. Pemilihan ini dikarenakan Umar dipandang progresif oleh
sebagian ulama, dari apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Misalnya
pada musim paceklik Umar tidak memotong tangan pencuri, Umar tidak lagi
mengasingkan pezina, Umar tidak lagi memberi sedekah kepada mualaf disaat
mualaf berada dalam kondisi yang sudah memadai. Umar menjatuhkan talak ba‟in
bagi yang mengucap satu kali untuk 3 talak, karena banyak suami yang suka
bermain-main, sementara hal tersebut tidak boleh dipermainkan.Mengingat apa
yang diputuskan Umar adalah sangat penting. Dan beberapa pandangannya hanya
dibaca serta dilihat dari kajian fikih (perdebatan antara teks dan konteks), dan juga
legalistik formalistik, maka perlu kajian lain yaitu etika (filsafat moral), sebagai
sebuah kajian interdisipliner dengan fikih. Dimana antara fikih dan etika ada
kesamaan objek kajian yaitu perilaku manusia, namun pada beberapa hal ada
perbedaan. Diantara perbedaannya yaitu etika lebih dominan menonjolkan
pemikiran rasio, dan hati nurani manusia.
Umar merupakan sahabat penting Nabi Muhammad Saw, yang langsung
mendapatkan pendidikan keIslaman dari Beliau. Dan juga, kondisi objektif yang
tengah dihadapi masyarakat terutama saat Umar menjadi seorang khalifah, dimana
wilayah dan masyarakatnya tidak hanya semata-mata masyarakat jazirah Arab,
tapi sudah menyebar ke hampir belahan Barat dan Timur (ekspansi masa Umar),
sehingga sudah mulai terasa banyaknya muncul permasalahan sosial keagamaan
yang sifatnya praksis dari pada permasalahan yang bersifat teologis. Dengan dasar
ini maka kebutuhan hukum sangat dominan, namun semata-mata hukum tanpa
pertimbangan dan menyoal, melihat dari sudut etika, hasil ijtihad Umar akan
menjadi timpang karenanya. Pada akhirnya akan mempertanyakan kredibilitas
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
251
Umar sebagai seorang yang pernah mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi
Muhammad Saw. Untuk itu agaknya perlu adanya penilaian etika pada ijtihad
Umar. Sehingga, proses pengembangan kerangka teoritik fikihnya tidak menjadi
terpisah dari etika.
Tujuan yang paling hakiki dari sebuah fikih adalah memberikan
penyadaran, kesadaran akan hakiki seorang manusia. Tujuan hakiki fikih adalah
memposisikan manusia kepada posisi manusia yang sesungguhnya. Karena itu
fikih bisa saja mengalami “pergerakan”. Dan, pergerakan fikih tentu diharapkan
tidak akan menciderai maksud tujuan serta etikanya. Disini penulis ingin
membaca dan melihat bahwa, adanya perubahan fikih itu tidak semata-mata
dilihat dari sisi legalistik formalistik putusan hukum saja, melainkan evolusi itu
juga mesti dibaca dan dilihat dari sisi dan konteks etika.
Dan apa yang dilarang masa Nabi Muhammad Saw menjadi dibolehkan,
atau sebaliknya apa yang dibolehkan menjadi dilarang di masa Umar. Poin ini
sangat penting, dan bukan masalah dilarang ataupun dibolehkan yang terkesan
berganti. Apa sesungguhnya maqas}id syari >’ah yang ada. Hakikat tujuan hukum
sebenarnya tidak hanya tentang hukum. Melainkan ada sisi-sisi pembelajaran,
penyadaran, dan pertimbangan etika. Penelitian ingin melihat sejak kapan sisi-sisi
perubahan etika itu terjadi. Kapan yang dimaksud di sini dalam proses
perubahannya, bukan soal waktu. Epistemologi pertimbangan apa yang ada
sehingga hukum-hukum fikih, sesungguhnya berubah pola menjadi hukum-
hukum etika. Ijtihad Umar bin Khattab pada permasalahan tentang hukum potong
tangan dengan penjelasan sebagai berikut:
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
252
Hukum Potong tangan pernah dipraktikkan dahulu pada masa jahiliyah,
lalu diakui oleh Islam dan ditambahkan syarat-syarat lainnya. Umar tidak
menghukum pencuri unta, yang menyembelihnya untuk makan dengan alasan
kelaparan. Umar hanya memerintahkan agar mereka membayar ganti rugi kepada
pemilik unta dua kali lipat dari harga unta. Umar membatalkan hukum potong
tangan terhadap mereka, karena pencurian terjadi di saat paceklik.562
Jadi sanksi
tidak dijatuhkan masa krisis atau paceklik. Allah berfirman dalam surat Al-
Maidah ayat (38), Artinya:
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”
Dalam ayat di atas, Allah Swt telah menetapkan dan memerintahkan untuk
memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, Umar tidak
menjatuhkannya pada sekelompok karyawan yang mencuri seekor unta, karena
majikannya tidak memberikannya upah yang wajar. Bahkan yang dijatuhi
hukuman ketika itu oleh Umar bin Khattab adalah sang majikan, yakni Ibn Hathib
Ibn Abi Balta‟ah, dengan mewajibkan membayar kepada pemilik unta yang dicuri
dua kali lipat harganya.563
Umar pun tidak memotong tangan orang yang mencuri
dari Baitul Mal. Ibnu Mas‟ud bertanya kepada Umar tentang jati diri siapa
pencurinya. Umar berkata, Bebaskanlah dia karena semua orang memiliki hak
dari harta yang terdapat di Baitul Mal ini. Kemudian Umar menghukumnya
dengan hukuman ta’zi >r berupa cambukan.564
562
Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar:
2008), 438. 563
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta,
Lenteng Hati: 2000), 196. 564 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
253
Dapat dipahami bahwa Umar menggugurkan hukuman dari beberapa
kasus yang telah disebutkan terdahulu juga bertolak dari adanya beberapa
pertimbangan. Bagi Umar bin Khattab tidak selamanya hukuman potong tangan
harus dilakukan. Surah al-Maidah ayat 38 dipahami dengan pengecualian seperti
yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. Penangguhan potong tangan juga
dilakukan dalam peperangan, larangan Nabi Muhammad Saw untuk memotong
tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh Umar agar pencuri ketika
itu tidak lari dan bergabung kepada musuh. Pertimbangan-pertimbangan semacam
itu jelas mempengaruhi pemikiran Umar dalam menerapkan ketentuan ayat
tersebut, sehingga penafsirannya tidak kering, dan selalu terpaut dengan teks-teks
aturan dalam Islam. Umar menegaskan, saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan
sanksi hukum, karena adanya dalih yang meringankan, daripada menjatuhkannya
secara keliru, padahal ada dalih meringankannya.565
Dalam hal ini hukum potong
tangan tidak serta merta dilakukan Umar, namun, juga turut melihat kepada
banyak hal. Situasi dan kondisi politik saat itu, situasi dan kondisi masyarakat
Muslim saat itu.
2. Beberapa Pendekatan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.
Dalam konteks inilah, muncul problema serius yang dirumuskan dalam
pertanyaan mendasar, bagaimana kita memahami dan melaksanakan fiqh
jina>yah sebagai bagian hukum Islam dalam konteks ke-Indonesia-an? Atau
dengan bahasa yang lebih lugas, bagaimana memasukkan (mengintegrasikan) fiqh
jina>yah sebagai bagian dari sistem tata hukum nasional bangsa Indonesia?
565 Ibid.., 198.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
254
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mudah. Sebab, banyak
asumsi yang berkembang di masyarakat baik dari kalangan umat Islam sendiri
maupun non-muslim terkait fiqh al-jina>yah itu sendiri; Pertama, dari kalangan
umat Islam terutama dari golongan kulturalistik memandang formalisasi hukum
Islam (termasuk fiqh al-jina>yah) akan membuka peluang intervensi negara
terhadap agama. Terlebih formalisasi hukum Islam yang dikhawatirkan akan
dijadikan alat penguasa untuk menindas umat Islam sendiri.566
Kedua,
kekhawatiran dari umat non-muslim jika fiqh al-jina>yah diadopsi menjadi
hukum nasional. Untuk melakukan formalisasi fiqh al-jina>yah sebagai hukum
nasional di Indonesia, bukanlah persoalan yang mudah. Paling tidak dilihat dari
dua aspek;
1. Realitas bangsa Indonesia yang plural harus dipertimbangkan.
2. Pembenahan dari aspek konsepsi, strategi dan metode perumusan fiqh al-
jina>yah, sehingga hukum pidana Islam yang dihasilkan meminjam istilah
Roscuo Pound, yaitu tidak bertentangan dengan kesadaran hukum
masyarakat Indonesia dan kompatibel dengan karakteristik tatanan hukum
nasional yang didambakan.
Disamping itu, upaya integrasi ini berjalan berdampingan pula dengan
upaya pembaharuan KUHP Indonesia yang dianggap sebagai peninggalan
kolonial Belanda dan out of date. KUHP yang berlaku sekarang ini, dianggap
kurang mewakili budaya Indonesia yang ketimuran dan dianggap pula tidak
memadai lagi untuk merespons perkembangan masyarakat dan peradabannya
yang sudah jauh berbeda. Dalam soal kesusilaan misalnya, KUHP masih
membolehkan hubungan seksual yang dilakukan secara suka sama suka, selama
kedua pelaku belum menikah, ataupun sudah menikah tetapi tidak ada aduan dari
suami atau isteri pelaku. Kendati didukung oleh sejumlah alasan kuat untuk
566 Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran
Gus Dur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
255
melakukan pembaharuan terhadap KUHP, upaya integrasi fiqh jinayah ke dalam
hukum pidana nasional masih sulit dilakukan. Perjalanan sejarah telah
membuktikan bahwa upaya integrasi tersebut berjalan di tempat. Upaya
penyusunan RUU KUHP yang telah dirintis sejak tahun 1963 sampai sekarang ini
masih belum dibahas di DPR, antara lain;
a. Perbaikan Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Sejarah telah mencatat, bahwa setelah merdeka bangsa Indonesia belum
memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri. Tetapi masih
memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda.
Kendati memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan
perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, semisal pergantian
nama: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi
dari Wetboek van Strafrechts, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari
Burgerlijk Wetboek dan lain-lain. Selain penggantian nama, beberapa pasal yang
dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka,
berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.567
Pendekatan semacam di atas dalam jangka pendek sangat bermanfaat
untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum). Akan tetapi,
untuk jangka panjang upaya “tambal sulam” atau transplantasi568
sejatinya kurang
efektif dan cenderung kontra produktif jika diberlakukan terus menerus. Dapat
567 Proses ini disebut Jaspan sebagai penggantian atau penambahan peraturan hukum ad hoc satu
per satu pada hukum kolonial. Lihat dalam M.A Jaspan, Mencari Hukum Baru: Sinkretisme
Hukum di Indonesia yang Membingungkan, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut,
Hukum, Politik dan Perubahan Sosial (Jakarta; Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 250-
251. 568 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta:
ELSAM dan HuMa, 2002), 250.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
256
dibayangkan tentunya apa yang akan terjadi jika hukum yang diberlakukan dalam
suatu negara tidak sesuai, menurut Friedrich Karl Von Savigny volksgeist atau an
expression of the common consciousness or spirit of a people.569
Bisa jadi akan
muncul penolakan atau paling tidak diabaikan oleh masyarakat itu sendiri. Tidak
mengherankan jika dalam muatan KUHP belum mengakomodir fiqh jinayah
sebagai hukum masyarakat mayoritas Indonesia. Dalam kasus zina misalnya,
KUHP tidak menganggap kasus zina ghairu muhsan (persetubuhan ilegal antara
dua orang yang belum menikah/tidak terikat dalam perkawinan, atas dasar suka
sama suka) sebagai suatu tindak pidana. “Zina” dalam KUHP hanya mencakup
persetubuhan ilegal antara dua orang, atau salah-satunya, yang sudah menikah.
Nampaknya, KUHP tidak melihat adanya unsur kejahatan pada kasus zina ghairu
muhsan, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Zina dapat merusak
tatanan masyarakat, bertentangan dengan akhlak yang mulia bertentangan dengan
agama, bahkan bertentangan dengan budaya nasional yang ketimuran. Delik zina
ini pun seharusnya bisa diubah dari delik aduan menjadi delik biasa.
Jika ditelusuri lebih dalam, ruang lingkup kajian fiqh Jinayah yang
mencakup aspek-aspek: pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina (al-
qadzaf), mengonsumsi barang yang memabukkan (khamr), membunuh atau
melukai, mencuri, merusak harta orang lain, jari>mah (melakukan kekacauan dan
semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan) dan jarimah dibagi dalam tiga
hal: qisa>s}/diyat , jari>mah hudu>d, dan jari>mah ta‟zi>r.570
Bentuk hukuman
yang diterapkan bagi pelaku pidana dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: hudud
569
Edwin M. Schur, Law and Society: A Sociological View (New York:Random House, 1968), 30. 570
Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 233. Uraian
lebih detail terkait tentang bidang pemidaan dalam fiqh jinayah bisa dalam karya Abdul Qadir
Audah.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
257
dan ta‟zir. Hudud adalah segala bentuk hukuman yang telah ditentukan oleh al-
Qur‟an dan Sunnah. Sedangkan ta‟zir „adalah bentuk hukuman yang tidak
ditentukan bentuknya oleh al-Quran dan Sunnah. Dalam kasus qisa>s} dan diyat ,
para ulama berbeda pendapat. Ada yang memandang qis}a>s dan diyat masuk
dalam kategori hudu>d. Namun mayoritas ulama berpandangan keduanya tidak
termasuk hudu>d.571
Qis}a>s} terkait dengan pembunuhan dan pencederaan anggota badan yang
pelakunya diancam dengan tindakan yang sama.572
Sementara diyat adalah ganti
rugi (denda) bagi pelaku tindak pidana ketika qis}>as} tidak jadi dilaksanakan karena
pemaafan dan bagi pembunuh semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan hudu>d
adalah haqqullah yang hukumannya telah pasti ketentuannya. Semisal had zina,573
had al-qadzaf,574
had as-sariqah (pencurian),575
had al-hira>bah (perampokan),576
had syurb al-khamr (pemabuk),577
had riddah (murtad) dan had al-baghyu
(pemberontak). Dan, ada satu bentuk hukuman lagi selain hudu>d dan ta’zi >r yakni
kifa>ra>t. Dari cakupan materi pemidanaan („uqu>bah) dalam fiqh jinayah sebagian
besar belum diakomodir dan dianggap delik pidana. Di antaranya adalah delik
meminum khamr, riddah dan baghyu belum menjadi delik pidana dalam KUHP.
Dan masih banyak pemidaan lainnya yang belum terakomodir.
571 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 10-14. 572 Lihat QS 2: 178, QS 5: 45, QS 4: 92. Ayat-ayat ini berbicara tentang qis}a>s dan diyat. 573 Had zina ada tiga bentuk hukuman yang diancamkan yaitu: hukum jilid (cambuk), pengasingan
(taghrib) bagi mereka yang ghairu muhshan (pezina yang belum menikah) dan rajam bagi pezina
yang sudah menikah. Lihat QS al-Nur ayat 2. 574 Hukuman (had) bagi qadzaf adalah didera delapan puluh kali dan kesaksiannya ditolak selama
hidup. Lihat QS al-Nur ayat 4. 575 Had pencuri adalah jelas dengan potongan tangan. Lihat QS al-Maidah ayat 38. 576 Had perampokan adalah dengan empat bentuk yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman mati
dengan penyaliban, (3) potong tangan dan kaki dan (4) pengusiran (al-nafyu). Hukuman ini
disesuaikan dengan kualitas kejahatan pelaku pidana. Lihat dalam QS al-Maidah ayat 33. 577
Had minum khamr tidak dinash-kan dalam Alqur‟an, namun dijelaskan hadits bahwa had-nya
adalah dera. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya. Imam Syafi‟i
berpendapat 40 kali dera, ulama lain ada yang mengatakan 80 kali dera.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
258
Tujuh materi pemidanaan („uqu>bah) yang masuk dalam kaegori hudu>d dan
bentuk hukuman yang kategori dalam ta’zi >r dipastikan bersifat delik pidana yang
di dalamnya mengandung motif kemaslahatan. Meski para pakar fiqh jinayah
berbeda pandangan terkait bentuk-bentuk hukuman dalam tujuh materi
pemidanaannya apakah bersifat pasti (qath’i>) ataukah dzanni>. Namun demikian,
dilihat dari jenisnya tujuh pemidanaan tersebut diakui para ulama adalah bersifat
pasti (qath’i>) masuk ke dalam tindakan pidana.578
Dengan demikian,
mengintegrasikan tujuh materi dalam pidana hudud ke dalam KUHP di Indonesia,
bagi penulis merupakan sebuah keniscayaan. Integrasi di sini dimaknai sebagai
upaya menjadikan fiqh jinayah bisa bertemu dengan hukum pidana nasional.
Integrasi jika menggunakan teori Ian G. Barbour adalah hubungan yang bertumpu
pada keyakinan bahwa pada dasarnya kawasan telaah, rancangan penghampiran
dan tujuan fiqh jinayah dan hukum nasional adalah sama dan satu. Singkatnya,
integrasi adalah kemitraan yang sistematis dan ekstensif antara fiqh jinayah yang
berbasis agama dengan hukum nasional sebagai hasil cipta karsa manusia.579
b. Aplikasi Pendekatan
Ketika membedah model ideal penerapan hukum Islam dalam praktik
kenegaraan, Bahtiar Effendy dalam disertasinya mengungkapkan setidaknya
adanya dua spektrum pemikiran yang saling berbeda. Pertama, mengatakan
bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan bahwa “Syari‟ah” harus diterima
sebagai konstitusi negara. Aliran ini juga mengatakan bahwa kedaulatan politik
ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan
dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik
578
Abdul Qa>dir Audah, al-Tasyrî> al-Jina>`î> al-Isla>mi>; Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wadh’i>, Beiru>t:
Mu’assasah ar-Risa>lah, 1996), Juz II. 579
Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: antara Sains dan Agama (Bandung: Mizan, 2005), 80-85.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
259
atau kedaerahan dan bahwa aplikasi prinsip syura berbeda dengan gagasan
demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata
lain, dalam konteks pandangan seperti ini, sistem politik modern diletakkan dalam
posisi yang berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam.580
Kedua, mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku
tentang teori negara yang harus dijalankan oleh ummah. Menurut aliran ini,
bahkan istilah negara (daulah)-pun tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an.581
Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-Qur‟an yang merujuk kepada
kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat
insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Menurut alur pemikiran
ini, Al-Qur‟an bukanlah buku tentang ilmu politik, tetapi lebih kepada kitab yang
mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang berkenaan
dengan aktivitas sosial dan politik umat manusia.
Model teoritis yang pertama, seperti yang telah dijelaskan di atas,
merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal
idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh
keinginan untuk menerapkan “Syari‟ah” secara langsung sebagai konstitusi
negara. Dalam konteks negara-bangsa yang ada dewasa ini seperti Turki, Mesir,
Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indonesia, model formal ini
mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern. Sebaliknya,
model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara
yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu, kecenderungan ini
mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendakatan yang dapat
580 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), iii-ix. 581 Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
260
menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara bangsa
merupakan salah-satu unsur utamanya. Hal ini mengingat esensi dari tujuan
disyari‟atkan hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam, untuk
menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan kehidupan manusia.
Disamping itu, hal lain yang juga tidak boleh diabaikan pertimbangannya
oleh umat Islam ialah bahwa KUHP baru yang diharapkan bisa menjadi wadah
akomodatif bagi pemberlakuan hukum pidana Islam yang dicita-citakan tersebut,
nantinya merupakan produk hukum nasional yang bersifat publik. Sehingga
dengan demikian pemberlakuannya akan menjangkau seluruh golongan penduduk
Indonesia, tidak hanya terhadap golongan umat Islam saja. Berdasarkan
pertimbangan demikian, maka gagasan yang menghendaki pemberlakuan hukum
pidana Islam secara formalistik, tentu harus dipikirkan ulang secara matang.582
Penerapan hukum pidana Islam dalam bentuk yang formal-tekstual, merupakan
sesuatu yang sangat sulit atau bahkan mustahil dan memerlukan perencanaan
yang matang dan berjangka panjang, serta realitas sosial-budaya yang kondusif.
Untuk saat ini, kondisi tersebut belum tercipta dan dengan demikian penerapan
hukum pidana Islam secara substansial-kontekstual merupakan pilihan yang
paling realistis.
c. Model Pendekatan
Integrasi fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional, ada beberapa
kendala yang harus dihadapi, yakni; Pertama, kendala historisitas. Berbeda
582
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari‟at Islam dalam Konteks
Modernitas, (Bandung: Asyaamil Press dan Grafika, 2001).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
261
dengan hukum-hukum Islam yang lainnya, bidang hukum publik (jinayah),
hukum Islam tidak diakui keberadaannya secara formal oleh Hindia Belanda.
Pemberlakuan hukum pidana Islam secara formal, akan berpotensi konflik dengan
kepentingan penjajah Belanda. Dalam beberapa hal, hukum Islam di bidang
hukum publik yang telah mentradisi dalam masyarakat, diberlakukan sebagai
hukum adat, bukan hukum Islam.583
Kedua, faktor sosial-budaya yang plural.
Pemaksaan penerapan hukum pidana Islam yang‟ “kaku” akan menimbulkan
gelombang protes dan permusuhan yang berkepanjangan, serta melanggar jaminan
negara bagi warga negaranya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan
keyakinannya masing-masing.584
Ketiga, faktor internal. Fiqh jinayah yang
dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, diwarnai dengan perbedaan yang cukup
tajam di antara beberapa mazhab. Hal ini belum ditambah lagi dengan perbedaan
kerangka berfikir di antara pemikir muslim berkaitan dengan hukum yang
ditetapkan dalam nas, al-Quran dan Hadis.
Misalnya penerapan hukuman rajam, potong tangan, cambuk, salib dan
lain sebagainya oleh sebagian fuqaha‟ dianggap sesuatu yang definitif dan tidak
dapat diubah, sedangkan menurut fuqaha yang lain, hukuman-hukuman tersebut
harus dipahami secara kontekstual.585
Dengan kata lain, hukuman-hukuman
tersebut dapat saja diubah, asalkan tujuan penjatuhan hukumannya mengenai
sasaran. Di samping itu juga hukum pidana Islam dianggap statis dan belum
komprehensif, karena kurangnya pengkajian dan pengembangan terhadapnya.
583 Mohammad Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). 584 Ibid.., 66-67. 585
Hartono Marjono, Menegakkan Syari‟at Hukum Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan,
(Bandung: Mizan, 1997).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
262
Formalisasi fiqh jinayah sebagai hukum nasional di Indonesia, bukanlah
persoalan yang mudah. Paling tidak dilihat dari dua aspek; Pertama, realitas
bangsa Indonesia yang plural harus dipertimbangkan. Kedua, pembenahan dari
aspek konsepsi, strategi dan metode perumusan fiqh jina>yah, sehingga hukum
Islam yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat
Indonesia dan kompatibel dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang
didambakan. Berangkat dari realitas di atas, maka agenda yang paling mendesak
untuk dilakukan adalah membongkar dan merajut kembali bangunan fiqh jina>yah.
Disadari bahwa bentuk-bentuk hukum fiqh jina>yah selama ini sarat dengan tradisi
hukum adat Arab pra-Islam. Karenanya untuk mempertemukan fiqh jina>yah dan
hukum nasional adalah mengkaji aspek epistemologi fiqh jina>yah Indonesia itu
sendiri. Karenanya, tulisan ini fokus dengan objek epistemologi.586
Sebab
epistemologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menjadi pijakan awal
penentuan asal muasal hukum. Singkatnya, sesuai fungsinya epistemologi sebagai
science of knowledge dan ilmu yang paling menentukan corak dan karakteristik
konstruksi sebuah ilmu pengetahuan (hukum).
Dengan demikian, maka terkait dengan metode hukum Islam, epistemologi
fiqh jinayah Indonesia harus mampu mengambil tradisi lama yang tentunya masih
relevan dengan tradisi modern dan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan modern dengan model integrasi maqashidy dan eklektisisme. Dalam
586 Epistemologi adalah salah satu dari tiga tiang penyangga yang dibahas dalam filsafat ilmu. Dua
lainnya yaitu ontologi dan aksiologi. Ontologi menyangkut tentang hakikat apa yang dikaji atau
“science of being qua”. Sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara ilmu pengetahuan
melakukan pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas
ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan. Yang terakhir aksiologi adalah untuk apa ilmu yang
telah tersusun tersebut dipergunakan atau lazim dikenal dengan “theory of value”. Lihat dalam
karya Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy, (Toronto, New Jersey: Littlefield Adam &
Co, 1976), 32.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
263
rangka memanfaatkan tradisi lama yang baik, epistemologi di Indonesia harus
mampu membangkitkan tiga nalar: bayani, burhani dan irfani sekaligus. Tentunya
dengan fokus pada kajian sosial-historis fiqh jinayah termasuk mengakomodasi
tradisi masyarakat lokal, rasionalisasi hukum Islam dan pengembangan teori
maslahat. Sesuai dengan kaidah al-Muha>faz}atu ala> al-qadi>mi al-s}alih wa al-
akhdzu bi jadi>d al-as}lah. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam berijtihad juga
menggunakan ilmu-ilmu alam dan sosial yang berkembang di Barat selama
perangkat keilmuan tersebut sesuai dengan problema hukum pidana yang dikaji.
1).Pendekatan Zawājir Ibra>hi>m Hosse>n.
Ibrahim Hosen lahir di Lampung 1 Januari 1917 dan wafat 7 November
2001.587
Secara formal, Ibrahim Hosen memulai pendidikannya pada Madrasah al-
Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura, kemudian melanjutkan pendidikan di
Mu'awanatul Khaer Arabische School (MAS) di Tanjung Karang Lampung yang
didirikan orang tuanya. Pada tahun 1932 dia melanjutkan sekolahnya di Teluk
Betung. Pada 1934, beliau belajar di beberapa pesantren di Jawa dan pada tahun
1955, ia Studi ke Universitas al-Azhar Kairo. Selama belajar di Mesir inilah, ia
dapat meraih Suahadah Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang Syari'ah
(LML). Ia ditahbiskan sebagai Mujtahid dari Ciputat oleh Majalah Tempo pada 1
Desember 1990. Sembilan belas tahun kemudian, atau tepatnya pada 6 Mei 2009,
Majalah Gatra menahbiskannya sebagai salah satu ilmuwan pelopor Indonesia:
Beliau dikenal sebagai Pakar ushul fikih (filsafat hukum Islam) dan fikih
perbandingan dan memimpin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua
dasawarsa (1981- 2000).
587 Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, Prof. KH.Ibrahim Hosen dan
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; CV. Tiga Sembilan, 1990), 1.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
264
Terkait dengan pendekatan legislasi al-fiqh al-jina>’i> paling tidak ada dua
model pendekatan yang dilakukan oleh para ahli hukum. Yaitu pendekatan
jawâbir (paksaan) dan pendekatan zawâjir (pencegahan). Pendekatan jawâbir
adalah menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang
secara tekstual literal disebutkan di dalam nash al-Qur‟an dan hadits. Semisal
potong tangan bagi pencuri, rajam dan jilid bagi pezina, cambuk bagi peminum
khamr dan sebagainya. Bentuk hukuman semacam ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.Pendekatan zawaj>ir ini
yang nampaknya dijadikan model penerapan perda syariat di ProvinsiNangroe
Aceh Darussalam yang dalam praktiknya banyak menuai badai kritikan dari para
pemikir hukum Islam khususnya di Indonesia.
Teori zawājir adalah teori yang dicetuskan Ibrahim Hossen seorang
pemikir Hukum Islam dari Indonesia. Terkait pembaruan hukum pidana Islam, ia
kemudian menawarkan pendekatan zawājir.588 Yakni Dalam pendekatan ini
hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak
harus persis atau sama bentuk hukumannya dengan apa yang secara tekstual
termaktub dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk
hukuman apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan
hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain
untuk melakukan tindakan pidana.589
Pendekatan zawājir memang mirip dengan teori batas (hudūd) yang
ditawarkan Syahrur. Perbedaannya, teori hudūd mempunyai kelemahan pada sisi
588
Nurrohman dan Marzuki Wahid, Formaslisasi Syari‟at Islam dan Fundamentalisme, Kasus
NanggroeAceh Darussalam dalam Jurnal Istiqro, Volume 01, Nomor 1, 2002, 45-74. 589 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 86-87. Lihat
juga dalam karya Ibrahim Hosen, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra
Harapan, 1990), 126-128.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
265
penetapan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai hukuman maksimal (hadd
a’la>). Dengan model yang demikian maka teori batas tidak bisa diterapkan dalam
segala bentuk ruang dan waktu. Sebab, jika pidana potong tangan dipandang
sebagai pidana yang maksimal, maka tujuan dari pemberian pidana agar membuat
jera bagi pelaku dan orang lain, dimungkinkan tidak tercapai. Dalam kasus
seorang pencuri kambuhan misalnya, tentunya pidana yang tepat tentunya tidak
cukup dengan dipotong tangannya. Pada titik inilah, pendekatan zawājir yang
sifatnya lebih umum akan lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Sebab dalam
pendekatan ini, hukuman bisa maksimal dan bisa minimal tergantung pada
kebutuhan.590
Teori zawa>jir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention.
Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak
lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation
theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan,
yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah
kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory).
Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharap efek
pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition),
misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya; dan intimidation
theory yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk
mengintimidasi mental si terpidana.591
Dalam rumusan ijtihadnya, khususnya pada bidang hukum pidana Islam,
Ibrahim Hosen menggunakan pendekatan taꞌaqqulī dari pada pendekatan
590
Bahtiar Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam
di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). 591
Ibid.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
266
ta‟abbudi (hukum Islam diterima apa adanya tanpa disertai komentar
(rasionalisasi). Pendekatan ta‟aqquli lebih menekankan rasionalisasi ajaran dalam
hukum Islam agar mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara simultan dalam
teori dan praktiknya secara bersamaan. Namun demikian, ia juga mengakui
terdapat ajaran hukum Islam yang bersifat ta‟abbudi> semata. Dan, ia tetap
menekankan agar ajaran yang selama ini dipandang taabbudī agar diteliti ulang
lebih lanjut, sehingga terbuka kesempatan untuk menjadikannya sebagai sesuatu
yang ta’aqquli>’ „dengan tetap berlandaskan pada maqās}id al-syarī’ah, pemahaman
„illat dan hikmah tasyrī‟.592”
Pendekatan taꞌaqqulī tercermin dalam pemikiran Ibrahim Hosen yang
menekankan aspek zawājir dalam penerapan hukum pidana Islam, terutama aspek
hudūd. Yaitu hukuman dilaksanakan dengan tujuan agar si-pelaku kejahatan
merasa jera dan tidak akan mengulangi lahi tindak pidana lagi. Atas dasar ini,
pezina tidak harus dihukum sesuai apa yang tertera dalam al-Qur‟an dan hadits.
Demikian halnya, pencuri bisa saja dihukum dengan hukuman selain potong
tangan, selagi hukuman tersebut mampu membuat jera pelaku. Lebih lanjut, ia
menyatakan bahwa sanksi-sanksi dalam hukum pidana Islam adalah lebih
berfungsi sebagai zawājir (penjeraan) bukan penghapus dosa (jawābir) hal ini bisa
dilihat dari adanya konsep pemaafan, baik dalam pertaubatan maupun pemaafan
dari korban, dalam hukum pidana Islam tersebut. Dalam pidana potong tangan
misalnya, hukum potong tangan hanya sebatas wasīlah (instrumen) bukan tujuan
utama (ghāyah).593
592
Juhaya S. Praja.., 95.
593 Ibid.., 96.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
267
Adapun metode ijtihad yang dipakai oleh Ibrahim Hosen adalah: (a)
Pemahaman kontekstual Alqur‟an dan Hadits (b) hanya menggunakan ijma
sahabat yang sharīh (jelas) (c) lebih menggunakan kaidah fiqh irtikāb akhaff al-
d}ararain dan kaidah hukm al-hākim ilzāmun wa yarfa’u al-khilāf dan (d) mem-
„fiqhkan hukum yang qath‟ī. Khusus metode terakhir, Ibrahim memandang bahwa
tidak semua hukum qath‟ī dalam ranah aplikasinya berlaku dalam segala ruang
danwaktu. Terkadang ia hanya berlaku dalam kondisi ruang, waktu dan kondisi
tertentu saja.
Terkait dengan pendekatan legislasi fiqh jinayah, ada dua model
pendekatan yang dilakukan oleh para ahli hukum. Yaitu pendekatan jawabir
(paksaan) dan pendekatan zawajir (pencegahan).594
Pendekatan jawabir adalah
menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang secara
tekstual literal disebutkan di dalam nash al-Qur‟an dan hadits. Semisal potong
tangan bagi pencuri, rajam dan jilid bagi pezina, cambuk bagi peminum khamr
dan sebagainya. Bentuk hukuman semacam ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
menebus dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.595
Pendekatan jawabir ini
yang nampaknya dijadikan model penerapan perda syariat di Provinsi Nangroe
594
Juhaya S. Praja, op. cit., 86-87. Lihat juga dalam karya Ibrahim Hosen, Pembaruan Hukum
Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Harapan, 1990), 126-128. 595
Disinilah letak perbedaan yang mendasar dalam hal melihat hubungan antara bentuk hukuman
dan tujuan hukuman dalam tradisi hukum pidana Islam dan hukum pidana Barat. Dalam hukum
pidana Islam, bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan mempunyai ekses
religius seperti pengampunan atas dosa disamping juga mempunyai motif untuk penjeraan bagi
pelaku supaya tidak melakukan/mengulangi kejahatannya kembali. Berbeda dengan tradisi
hukum pidana Barat yang hanya bertujuan untuk ekses penjeraan. Untuk lebih detail baca
Muhari Agus Susanto, Paradigma Baru Hukum Pidana (Malang: Pustaka Pelajar dan Averroes
Press 2002).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
268
Aceh Darussalam yang dalam praktiknya banyak menuai badai kritikan dari para
pemikir hukum Islam.596
Pendekatan yang lebih elegan yang lebih kompatibel jika diterapkan di
Indonesia, adalah pendekatan zawa>jir. Dalam pendekatan ini, epistemologi fiqh
jina>yah Indonesia, hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku
tindak pidana tidak harus persis atau sama dengan apa yang secara tekstual
tercantum dalam Alqur‟an dan hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk
hukuman apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan
hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain
untuk melakukan tindakan pidana.
Pendekatan zawa>jir mirip dengan teori batas (hudu>d) yang ditawarkan
Syahrur. Perbedaannya, teori hudud mempunyai kelemahan pada sisi penetapan
hukum potong tangan bagi pencuri sebagai hukuman maksimal (hadd al-a’la>).
Dengan model yang demikian maka teori batas tidak bisa diterapkan dalam segala
bentuk ruang dan waktu. Sebab, jika hukuman potong tangan dipandang sebagai
hukuman yang maksimal, maka tujuan dari pemberian hukuman agar membuat
jera bagi pelaku dan orang lain, dimungkinkan tidak tercapai. Dalam kasus
seorang pencuri kambuhan misalnya, tentunya hukuman yang tepat tentunya tidak
cukup dengan dipotong tangannya. Pada titik inilah, pendekatan zawajir yang
sifatnya lebih umum akan lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Sebab dalam
596 Lihat Perda NAD Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.5/2000 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam, Perda/Qanun NAD No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Qanun
No. 11/2002 tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh, Qanun NAD No.
12/2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Perda/Qanun NAD No. 13/2003 tentang
Maisir (perjudian), Perda/Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
269
pendekatan ini, hukuman bisa maksimal dan bisa minimal tergantung pada
kebutuhan.597
Ada korelasi kuat antara bentuk hukuman dan tingkat kejeraan para pelaku
tindak pidana. Hanya saja, dalam kasus hukum potong tangan yang terdapat dalam
fiqh jina>yah, Epistemologi hukum Indonesia tidak menjadikannya sebagai satu-
satunya bentuk hukuman yang diterapkan. Namun bisa saja dalam bentuk yang
lebih berat, hukuman mati misalnya, atau justru bisa jadi lebih ringan. Semuanya
tergantung pada kondisi objektif lingkungan dan pelaku. Kondisi objektif
lingkungan bisa saja berkaitan dengan tradisi (proses pidana) yang terdapat dalam
suatu masyarakat atau kondisi sosial-ekonomi dan faktor lainnya. Sedang kondisi
objektif pelaku bisa saja berkaitan dengan tingkat kesadaran beragama dan tingkat
sosial ekonomi. Kedua kondisi objektif tersebut, merupakan faktor yang paling
menentukan untuk pemberian hukuman berat, sedang atau ringan.
Berbeda lagi jika masalah hukum pidana dibicarakan dalam konteks
keindonesiaan. Di masyarakat Lampung misalnya, orang yang membunuh dapat
dituntut balas untuk dibunuh juga. Demikian di Papua, Madura dan lain-lainnya.
Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dalam perspektif fiqh jinayah ada kesamaan
dengan qis}a>s selain juga harus membayar denda yang sama dengan hukuman
diyat . Dan memungkinkan pula bisa dimaafkan tanpa kompensasi apapun. Dalam
597
Teori zawa>jir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention; Artinya, hukuman pidana
harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk
melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan
dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat
merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori
ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharp efek pencegahan dapat
timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, contoh
keteladanan dan sebagainya; dan intimidation theory yang memandang bahwa pemidanaan itu
merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Lihat dalam karya Bahtiar Effendy,
Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia,
(Jakarta: Paramadina, 1998).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
270
kasus masyarakat Lampung dan Papua misalnya seseorang pembunuh bisa bebas
bahkan menjadi kerabat terbunuh setelah sebelumnya melakukan ritual tertentu.
Semisal menyembelih kerbau dalam kasus masyarakat Lampung dan memotong
babi bagi masyarakat Papua. Kesadaran-kesadaran sosiologis-historis semacam
inilah yang mestinya dipahami betul oleh para ahli hukum kita. Dengan model
pendekatan semacam inilah upaya memasukkan fiqh jinayah ke dalam rancangan
KUHP baru lebih mudah dilakukan.
Dalam konteks kajian fiqh jinayah ke-Indonesiaan, epistemologinya lebih
memilih untuk melakukan upaya akomodasi akan adat dan tradisi hukum pidana
lokal (local wisdom) yang berkembang. Tentunya setelah dilakukannya
objektivikasi baik dari aspek istilah-istilah teknis dan bentuk-bentuk hukumannya.
Dari apek peristilahan sedapat mungkin tidak menggunakan istilah atau huruf
Arab dan dari aspek bentuk dapat dikompromikan dengan teori-teori pemidanaan
modern. Upaya objektivikasi ini bukan bertuj uan untuk menghilangkan fiqh
jinayah itu sendiri. Melainkan semata-mata untuk menghindari kesalahpahaman
yang tiada perlu. Dengan metode ini diharapkan fiqh jinayah secara substansial
tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat muslim, meski simbol-formal tidak
begitu nampak di permukaan. Inilah yang menurut penulis sesuai dengan kaidah
ma> la> yudraku kulluhu> la yutraku kulluhu>.
2). Teori Dekonstruksi Syari’ah al-Naꞌim
Abdullahi Ahmed An-Naꞌim, lahir 6 April 1946 di daerah Mawaqier 200
km dari utara Khartoum Sudan. Setamat dari pendidikan SLTA, ia melanjutkan
studi di fakultas Hukum Universitas Khartoum (1965-70) dengan gelar LL.B dan
pada 1973 meraih gelar LL.M dan gelar MA diraihnya pada tahun 1976. Dan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
271
puncaknya, pada 1976 Abdullahi mampu meraih gelar Ph.D dalam bidang ilmu
hukum dari Universitas Edinburg, Skotlandia.598
Teori yang diusungnya dikenal dengan konsep “dekonstruksi syari‟ah”.
Menurutnya, syariꞌah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanya
interpretasi terhadap teks dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks historis
tertentu. Penafsiran dan praktik keberagamaan, tidak dapat dilepaskan dari kondisi
sosiologis, ekonomi dan politik masyarakat tertentu, tentu saja ada variasi dan
kekhasan lokal, demikian hal-nya sistem hukum agama seperti syariah. dengan
demikian, syariah yang telah disusun oleh para ahli hukum perintis dapat
direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, dengan catatan tetap berdasarkan pada
sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan
agama. Karenanya, An-Na‟im menggugat sakralisasi hasil pemahaman syariah
historis, terlebih ia menilai syariah, sudah tidak lagi memadai dan tidak adil,
padahal syariah dipandang umat Islam merupakan bagian dari keimanan.599
Dalam melakukan pembaruan teori-teori hukum publik Islam, An-Na‟im
berangkat dan menggunakan teori gurunya Mahmoud Mohammed Taha yang
dikenal dengan teori naskh atau teori “naskh terbalik”. Teori ini sejatinya
merupakan bentuk upaya rekonstruksi dari metode nasakh600
yang sudah mapan
598 Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Mahmud Muhammad Taha and Crisis in Islamic Law Reform:
Implications for Interreligious Relations, Journalof Ecumential Studies 25: 1 (1988), 177. 599 Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights
and International Law‟ „(New York: Syracuse UniversityPress, 1996), xiv dan Lihat juga
Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Islam dan NegaraSekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syari‟ah,
terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan,1997), 27. 600
Ada beberapa ayat dalam al-Qur‟an yang muatan hukumnya muncul belakangan, maksudnya
ayat turunnya terlebih dahulu, kemudian hukum-hukum syariah dan fiqh yang terkandung di
dalamnya baru bisa diterapkan belakangan. Sehingga melahirkan metode naskh. Termasuk
kesepakatan bahwa banyak ayat-ayat makkiyah yang dihapus oleh ayat-ayat madaniyyah. Terkait
kategorisasi di atas, ada tiga pandangan ulama ushul fiqh ketika mendiskusikan ayat-ayat
makkiyyah dan madaniyyah dengan pandangan sebagai berikut: pertama, sebagian ulama
berpendapat bahwa ayat-ayat makkiyah diturunkan sebelum Nabi Hijrah, sedang ayat-ayat
madaniyyah diturunkan sesudah Hijrah. Kedua, Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat-ayat
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
272
dalam kajian us}ūl al-fiqh. Pendekatan rekonstruktif ini, An-Na‟im tempuh dalam
rangka menyesuaikan nash-nash al-Qur‟an dan al-Sunnah dengan kondisi modern.
Hal ini dilakukan guna memenuhi tuntutan penerapan Alqur‟an dan al-Sunnah.
Karenanya, perlu interpretasi yang memadai agar semangat yang dikandungnya
dapat ditangkap.601
An-Na‟im berpendapat bahwa hukum publik (pidana) Islam terutama
aspek hudu>d, qisās dan yang sejenisnya, dinilai dapat dijadikan landasan dan
konsisten dengan konteks historisnya. Namun, menurutnya, tidak dapat dijadikan
alasan dan (tidak secara) konsisten bersesuaian dengan konteks kekinian.
Berbagai aspek pada hukum publik syariah dalam konteks politik tidak lagi akurat
atau tidak lagi fungsional.602
Baginya yang sempurna adalah yang selalu
melakukan perubahan dan perkembangan. Kesempurnaan manusia ia ilustrasikan
dengan kondisi Tuhan yang selalu memperbarui diri-Nya. Sebagaimana dalam
surat ar-Rahman ayat 29.
An-Na‟im berpendapat bahwa hukum publik terutama pidana, yang tepat
untuk di implementasikan saat ini adalah hukum Islam yang berdasarkan realitas
konkret, bukan hukum Tuhan semata. Sehingga dapat menyelesaikan masalah dan
tepat sasaran. Standar kesahihan dan ketepatannya adalah pembelaan nilai-nilai
kemanusiaan dengan didukung oleh dua argumen: argumen yang bersifat moral
dan argumen yang bersifat empiris. Dalam teori dekonstruksinya, an-Na‟im
menekankan prinsip resiprositas dan mengikuti praktik-praktik kehidupan bangsa-
makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah, meski Nabi sudah hijrah. Ketiga,
sebagian lagi ulama menentukan dari sisi isi dan tujuan ayat-ayat tersebut. Biasanya ayat-ayat
makkiyyah diawali dengan redaksi “ya ayyuha al-nas” sedangkan ayat-ayat madaniyyah diawali
dengan ya ayyuhal ladzina amanu.. Lihat dalam Mabahist fi Ulum al-Qur‟an, karya Manna‟ al-
Qathhan, (t.tp, Mansyurat al-„Ashr al-Hadits, t.th.), 56. 601 A.Luthfi Assyaukanie, Tipologi dan wacana Pemikiran Arab Kontemporer dalam Jurnal
Pemikiran Islam Paramadina, vol. 1, No. 1, 1998. 602
Abdullahi Ahmed am-Na‟im.., 34.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
273
bangsa modern. Umat Islam boleh menerapkan hukum Islam dengan catatan tidak
melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain. Karena itu, yang
bisa dilakukan adalah membangun hukum pidana Islam alternatif. Dalam
kerangka inilah maka yang dibutuhkan adalah melakukan reinterpretasi teks-teks
hukum publik (pidana) syari‟ah.
3. Prospek Pendekatan Restoratif Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan
Hukum Pidana Nasional.
Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia agak tersendat dengan
berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda
berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam
secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.
Dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia digambarkan dengan
munculnya berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli (sejarawan), seperti
teori penerimaan autoritas hukum dari H.A.R. Gibb, teori receptio in complexu
dari L.W.C. van den Berg, teori receptie dari C. Snouck Hurgronje yang
kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar,603
teori receptie
exit dari Hazairin, dan teori receptio acontrario dari Sajuti Thalib.604
Sejak pemerintah Belanda hengkang dari bumi nusantara, keberadaan
hukum Islam mulai dianggap signifikan dan mendapat perhatian yang baik di
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Usaha
mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya seperti
semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan.
603
Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991), 122. 604 Ibid.., 133.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
274
Perjuangan mereka dimulai sejak peletakan hukum dasar bagi negara kita, yaitu
ketika mereka dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah bertukar pikiran melalui musyawarah,
para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus UUD Republik
Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 mencapai persetujuan yang
dituangkan ke dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam
Jakarta (22 Juni 1945). Dalam Piagam Jakarta, yang kemudian diterima menjadi
Pembukaan UUD 1945, dinyatakan antara lain bahwa negara berdasar kepada
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini kemudian oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dihilangkan dan diganti dengan kata Yang Maha
esa.605
Meskipun usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar
nasional tidak berhasil pada waktu itu, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya
berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam untuk
menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam pembangunan
hukum nasional. Dalam hal ini hukum Islam banyak memberi kontribusi yang
berarti bagi pembangunan hukum nasional. Beberapa contoh mengenai hal ini bisa
disebutkan seperti dalam pembuatan UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974, UU
Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) yang dilanjutkan dengan
pemberlakuan UU Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989), UU Pokok Agraria
(UU No. 5 tahun 1960), UU Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961), dan UU
Pokok Kepolisian (UU No. 13 tahun 1961).
605 Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta:
LP3ES, 1989), 231.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
275
Pada tahun 1991 pemerintah Indonesia memberlakukan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991. KHI ini terdiri
dari tiga buku yang semuanya merupakan bagian dari hukum perdata Islam, yakni
buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku
III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini merupakan pegangan para hakim agama
dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya di
Pengadilan Agama. KHI ini hanya berlaku bagi umat Islam yang berperkara
dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa KHI yang merupakan kumpulan aturan-
aturan mengenai hukum Islam di Indonesia belum menjangkau semua bidang
yang ada dalam bagian hukum Islam. Salah satu bidang yang sama sekali tidak
disinggung dalam hal ini adalah hukum pidana Islam. Oleh karena itu, jika umat
Islam berperkara dalam hal pidana atau kriminal, tidak bisa ditemukan aturannya
dalam KHI tersebut, bahkan Pengadilan Agama, tempat diterapkannya KHI, tidak
mempunyai wewenang mengadili masalah-masalah yang menyangkut pidana
yang dilakukan oleh umat Islam. Hukum pidana yang diberlakukan sekarang
nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut,
tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan
taktik yang lebih canggih untuk dapat terhindar dari jeratan hukum pidana yang
ada. Kalaupun sampai dipidana, para pelaku kejahatan tidak mendapatkan sanksi
hukum yang berat.
a. Perkembangan Restorative Justice.
Kemajauan di bidang Ilmu hukum pengetahuan hukum pada akhir abad 20
memiliki ciri sebagai berikut;
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
276
1. Humanittarian Law, hukum tidak bebas nilai dari asaskemanusiaan bagi
semua individu (Human Right), baik yang dirumuskan dalam konvensi
maupun hukum positif yng berlaku;
2. Law and Civilizasions, bukan hukum yang bersifat konfrontatif,melainkan
hukum yang mengadung unsur peradaban yang semakin maju;
3. Law as a part on human welfare, hukum harus dapatmemberikan
kesejahteraan bersama (sosial welfare) dan pelayanan hukum bagi
masyarakat banyak dengan merasionalisasikan sanksi penal;
4. Law and Morral, tatanan hidup mansusia tidak dapatmengesampingkan
begitu saja terhadap norma dan moral, yang dikomplementasikan dengan
norma hukum.606
Menarik sekali jika ini, dikiaskan kepada hukum di Indonesia sebagai
bahan dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dengan penerapan
konsep penal mediations/restorative justice. Mediasi sebagai salah satu
pendekatan restorative justice memiliki akar sejarah yang panjang dalam
menaggulangi tindak pidana. Mediasi pidana merupakan bentuk kuno dari
penanganan perkara pidana di dalam masyarakat. Pendekatan restorative justice607
sering dipertentangkan dengan pendekatan retributive justice dalam
penanggulangan tindak pidana. Pertentang tersebut terlihat dari sudut pandang
kedua pendekatan tersebut. Para pendukung restorative justice berpendapat respon
utama Negara pada kejahatan seharusnya adalah menghukum pelaku kejahatan
setimpal dengan perbuatannya.608
606
Imron Anwari, Penerapan Hukum pidana Kini dan Masa Mendatang, (Genta Publishing
Yogyakarta, 2014), 176. 607
Seumas Miller dan John Blackler, Restorative Justice: Retribution, Confession and Shame,
sebagaimana dirangkum dalam buku Restorative Justice Philosophy to Practice, editor: Heather
Strang dan John Braitwaite, (Inggris: Dartmouth Publishing Company, 2000), 88. Terjemahan
bebas dari penulis yaitu: Keadilan restoratif sering berbanding terbalik dengan keadilan
retributif, dengan alasan bahwa dasar retributive itu diadakan untuk berkomitmen kepada
hukuman untuk kepentingan diri sendiri, kemudain meninggalkan hukuman yang membuat
malu, rekonsiliasi dan pengampunan. Kami akan berpendapat bahwa ada peran ineliminable
untuk prinsip-prinsip keadilan retributif, termasuk hukuman, dalam konsep keadilan restoratif.
Kami selanjutnya akan berpendapat bahwa konsep rasa malu yang lebih dekat terkait dengan
hukuman. Akibatnya, rasa malu dan hukuman bukan alternatif, namun berjalan beriringan dalam
kerangka keadilan restoratif dapat diterima. 608 R.A. Duff, “Restorations and Retribution”, dalam Von Hirschi et.el.,Restoration Justice and
Criminal Justice, (Hart Publishing, 2003), 43.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
277
Sistem peradilan pidana dianggap kurang mendominasi semua
kepentingan masyarakat, dan mengabaikan kepentingan korban. Korban hampir
tidak memiliki peran atau kontrol dalam proses peradilan pidana yang pada
akhirnya tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh pengadilan. Melalui
restorasi terdapat pengakuan oleh pelaku tindak pidana sebagai penyebab
terjadinya luka terhadap diri korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana
memberikan kepada korban apa yang diperlukan untuk menghilangkan rasa sakit.
Pelaku tindak pidana pada akhirnya akan memberikan tanggung jawab secara
langsung kepada korban tindak pidana, sehingga membuat segalanya menjadi
lebih baik kembali.609
Artinya pendekatan restorative justice melihat tindak
pidana sebagai bentuk pelanggaran kepada manusia sebagai individu dan
merupakan hubungan interpersonal.610
“Pendekatan restorative justice melihat adanya kerugian yang diderita
akibat tindak pidana oleh para pihak baik korban, masyarakat dan pelaku tindak
pidana. Pendekatan restorative justice mengupayakan keseimbangan kepentingan
para pihak dalam tidak pidana dan memberikan ganti kerugian yang muncul dari
adanya tindak pidana guna mencapai keadilan. Pendekatan tersebut yang
mengutamakan keseimbangan ini mengingatkan peran korban, masyarakat dan
pelaku tindak pidana. Pendekatan yang seimbang tersebut mempunyai tiga tujuan:
pertama, tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korban dan masyarakat;
609
Mark S. Umbreit et al, Responsive Justice in the Twenty-first Century: A Sosial Movement Full
of Opportunitas and Piffalls, Sysmposium: Restorative Justice in actions, (Marquette Law
Riview, 2005), 257. 610
Pendekatan restorative Justice yang menekankan pada hubungan interpersonal, bertentangan
dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan yang diselenggarakan oleh
Negara, sebab tindak pidana telah berubah menjadi perbutan yang merusak dan menggangu
kedamaian Negara secara umum, Negara sacara pasti mengambil alih konflik antara pelaku dan
koabn tindak pidana dari permasalahan antara individu menjadi permasalahan publik.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
278
kedua, kemampuan pelaku untuk berkembang dan ketiga, perlindungan pada
masyarakat.611
Sementara ini, di di Indonesia sendiri hukum pidana lebih difokuskan pada
persoalan penanganan pelaku. Hukum pidana diorientasikan memberikan
hukuman yang mampu mendidik pelaku, mengembalikannya sebagai seorang
yang bermanfaat dalam masyarakat selaindia menjadi jera. Ternyata dalam
praktek tujuan tersebut tidak juga terwujud karena pihak-pihak yang langsung
bersinggungan tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian
persoalan seperti korban maupun masyarakat. Seorang penjahat yang selesai
menjalani hukuman seringkali masih menerima hukuman dari masyarakat berupa
pengecilan dan stigma buruk. Hal ini terjadi, karena masyarakat tidak
pernahterlibat dalam proses perbaikan diri pelaku kejahatan.
Restorative justice memberikan satu alternatif penyelesaian pidana dengan
cara yang lebih bernilai kepada perdamaian dan pemulihan. Berdasarkan pada
perkembangan falsafah pemidanaan di atas, maka sudah semestinya saat ini ide
pemidanaan harus terus berkembang seiring dengan berkembangnya falsafah
pemidanaan tersebut. Perspektif pembalasan menurut hemat penulis semata-mata
sudah lama ditinggalkan, pespektif relatif sudah mulai kehilangan relevasansinya
karena masalah efektifitas pada aspek penjeraan bagi pelaku tindak pidana.
Sementara perspektif gabungan dipertanyakan konsistensinya karena memiliki
dua dasar asumsi yang berbeda. Sementara restoratif yang berorientasi kepada
korban dan penyelesaian bersama dengan tujuan pemulihan masih perlu diuji
efektifitasnya di Indonesia.
611
Kathy Elton dan Michele M Rybal, Restorative a Componentof Justice, (Utah Law Riview,
2003), 50.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
279
C. Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Fenomena penegakan hukum di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah
memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum yang menimbulkan
kontroversi, polemik, bentuk perlawanan, protes atau kritik tajam dari berbagai
pihak. Misalnya, berbagai kasus aktual yang menarik seperti : Kasus nenek Minah
yang berusia lima puluh lima tahun, Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan
Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang dituduh mencuri 3 biji buah kakao di PT.
Rumpun Sari Antan 4 di desa Darmakradenan yang kemudian Pengadilan Negeri
Purwokerto, Jawa Tengah menvonis pidana penjara selama satu bulan lima belas
hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa.
Kasus tersebut merupakan masalah aktual hukum pidana yang bersifat
represif, tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Hal ini seringkali
menimbulkan reaksi, kontroversi dan sorotan yang sangat tajam kepada aparat
penegak hukum dengan berbagai sudut pandang dan argumentasi masing-masing.
Sebagian pihak menganggap bahwa aparat penegak hukum terjebak dalam
pikiran-pikiran hukum normatif, bahwa hukum memberi kesan angker dan
menakutkan untuk masyarakat.
1. Transformasi Restorative Justice Hukum Pidana Islam Bagi Pembaruan
Hukum Pidana Nasional.
Transformasi fiqh jina>yah ke dalam hukum pidana nasional saat ini
sesuatu yang seharusnya niscaya.612
Hal tersebut bukan saja karena mayoritas
612
Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia telah membuat rancangan undang-undang Hukum
Pidana terdiri dari 647 pasal yang dalam beberapa pasalnya telah memasukkan fiqh jinayah ke
dalam kitab tersebut. Namun demikian, hingga saat ini kitab undang-undang tersebut masih
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
280
masyarakat Indonesia adalah muslim, tetapi juga karena secara historis fiqh
jina>yah Islam pernah hidup di bumi Indonesia. Namun demikian, hukum pidana
Islam (fiqh al-jina>yah) yang ditawarkan harus hukum pidana yang dinamis, elastis
sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang pluralistik, tanpa mengabaikan
tujuan-tujuan syariah. Upaya ini akan menemui sejumlah problem, semisal
problem historisitas, sosial-budaya, institusional dan kendala internal hukum
pidana Islam sendiri. Kendala-kendala ini harus dicarikan solusinya agar
transformasi ini dapat berjalan dengan baik. Mempertimbangkan problem-
problem di atas, maka model penerapan hukum pidana Islam yang paling tepat
adalah dengan mengkompromikan fiqh al-jina>yah dengan hukum pidana (warisan
Belanda) yang berlaku saat sekarang ini. Artinya, penerapannya tidak harus
formal-tekstual, akan tetapi substansial-kontekstual. Dengan demikian, hukum
pidana Indonesia mendatang benar-benar dapat diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat dan diharapkan mampu membentuk masyarakat Indonesia, yang taat
hukum serta berakhlak mulia. Dengan metode ini diharapn diharapkan fiqh
jinayah secara substansial tetap bisa menjadi bagian dari masyarakat muslim,
meski simbol-formal tidak begitu nampak di permukaan. Inilah yang paling sesuai
dengan kaidah ma> la> yudraku kulluhu> la yutraku kulluhu>.
Dalam Rekonstruksi epistemologi fiqh jinayah Indonesia, gagasan
transformasi tersebut harus dipetakan, mana wilayah fiqh jinayah yang substansial
(qath‟i) dan mana yang parsial (dzanny). Dalam konteks dan dan bidang hudud
misalnya, tujuh bidang: zina, qadzaf, syurb al-khamr dan yang lainnya delik
sebatas draf yang belum disahkan oleh DPR. Lebih detainya lihat Ahmad Djazuli, Ilmu fiqh;
Penggalian dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 193-194.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
281
pidana sudah saatnya dicover dalam hukum pidana nasional. Namun dalam hal
bentuk hukuman tidak harus sama dengan tawaran al-Qur‟an. Sebab hukuman
potong tangan, rajam dan sebagainya merupakan wasilah bukan ghayah.
Dalam titik inilah menarik mencermati gagasan Ibrahim Hosen yang
menekankan pendekatan ta‟aqquli> dalam hukum pidana Islam. Pendekatan ini
sangat penting dalam mengedepankan aspek zawajir-nya.613
Yakni hukuman
dilakukan agar pelaku pidana merasa jera, tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut. Dengan demikian maka bentuk hukuman tidak terikat pada bunyi teks
(nash). Atas dasar ini seorang pencuri bisa saja dihukum selain potong tangan.
Asalkan hukuman tersebut mampu membuat jera pelaku dan tidak akan
mengulanginya lagi dan membuat orang lain takut. Demikian halnya dengan
hukuman pelaku tindak pidana hudud lainnya. Ibrahim Hosen dipandang orang
yang setuju bahwa sanksi hukum bentuk potong tangan dan rajam tidak relevan
diterapkan di Indonesia. Menurutnya, potong tangan, dera dan rajam bukanlah
tujuan hukum itu sendiri, melainkan sebagai instrumen agar membuat pelaku
pidana jera. Karenanya dalam konteks ini, syariat menjadi relatif, bisa dirubah dan
dikontekstualisasikan.614
Lebih lanjut, menurut Hosen, hukum tidak bergantung
pada sebuah benda atau barang yang dihasilkan, tetapi terkait dengan perbuatan
manusia (mukallaf). Dan, pemutusan sebuah hukum sangat terkait dengan masa>lik
al-‘illat.
613
http://fai.uhamka.ac.id diunduh tanggal 20 September 2020.
614 http://fai.uhamka.ac.id diunduh tanggal 20 September 2020. Pandangan Hosen tentang zawajir
ditentang keras oleh Satria Effendi. Menurut Effendi, dalam hukum potong tangan terdapat
fungsi jawabir dan zawajir. Menanggapi reaksi ini Hosen mengatakan bahwa ia merupakan
wasilah bukan tujuan atau ghayah.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
282
Dengan epistemologi demikian, maka transformasi fiqh jinayah menjadi
hukum nasional terbuka untuk diterima masyarakat Indonesia. Dalam kasus zina
misalnya, KUHP tidak menganggap kasus zina ghairu muhsan (persetubuhan
ilegal antara dua orang yang belum menikah atau tidak terikat dalam perkawinan,
atas dasar suka sama suka) sebagai suatu tindak pidana. Zina dalam KUHP hanya
mencakup persetubuhan ilegal antara dua orang, atau salah-satunya, yang sudah
menikah. Tampaknya, KUHP tidak melihat adanya unsur kejahatan pada kasus
zina ghairu muhsan, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Secara sekilas
mungkin benar, akan tetapi jika dikaji lebih jauh, perbuatan tersebut bukan saja
akan merugikan keluarga dan masyarakat setempat, bahkan kedua pelaku tersebut.
Delik zina ini pun seharusnya bisa diubah dari delik aduan menjadi delik biasa.
Dilihat dari segi bentuk hukuman fiqh jinayah sering mendapat kritik
akibat masih diterapkannya ketentuan rajam (melempar dengan batu sampai
terpidana meninggal) dan jilid (cambuk). Dalam hukum Islam belakangan ini
diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam
dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang
melatarbelakangi lahirnya teori jawabir . Namun, telah muncul teori baru yang
menyatakanbahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi
orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini
dikenal dengan teori zawajir. Jadi, bagi penganut teori jawabir, hukuman potong
tangan dan qisas itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nash, sedangkan penganut
teori zawajir berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan
hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu
membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
283
Dengan demikian, bentuk-bentuk hukuman fisik, seperti rajam dan potong
tangan, sedapat mungkin dihindari atau diberikan kriteria yang ekstra ketat dan
memenuhi tujuan penjatuhan hukuman tersebut yaitu represif dan preventif. Di
samping hal-hal di atas, konstribusi hukum pidana Islam juga bisa diberikan
dalam bentuk asas-asas yang disarikan dari hukum pidana Islam. Asas-asas ini
kemudian dijadikan sebagai asas hukum materiil yang konstitutif, artinya masuk
dalam KUHP, dan dijadikan perspektif dalam pembentukan hukum pidana
nasional. Berdasarkan uraian diatas, maka;
1. Teori pembaruan dalam hukum pidana Islam mempunyai daya murunah
(dinamis) dalam merespons dinamika perubahan hukum yang begitu cepat;
2. Pembaruan teori pemidanaan dalam hukum Islam merupakan jalan yang
ideal dalam menemukan “titik temu” antara pemidanaan Islam dengan
teori pemidanaan kontemporer. Dengan demikian pada gilirannya, hukum
pidana Islam dapat dikembangkan dalam konteks pembangunan hukum
nasional;
3. Pembangunan hukum Pidana Islam paling ideal dilakukan dengan
pendekatan maqashidy istishlahy; Artinya, untuk menyatukan fiqh jinayah
dengan hukum pidana nasional.
Dengan demikian maka epistemologi fiqh jinayah Indonesia mendukung
desimbolisasi dan objektivikasi pidana Islam selama dalam koridor menjaga dan
meruwat maqashid al-syari‟ah. Dengan metode penentuan prinsip-prinsip
fundamental dan universal inilah, niscaya fiqh jinayah dapat ditransformasikan ke
dalam Hukum Pidana Nasional.
2.Restorative Justice dalam Peradilan di Indonesia.
Peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang semula dianggap sebagai karya
agung ternyata masih ada kekurangan. Hal ini nampak dari ketentuan tambahan di
luar KUHAP seperti P18, P19 dan P21 untuk mengatur hubungan kerja antara
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
284
penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) yang seharusnya saling tergantung
menjadi penyidik ”tergantung” „kepada penuntut umum. Di sisi lain dalam
praktek penegakan hukum, secara substantif terdapat ketidakmampuan (unability)
dan ketidakmauan (unwillingness) aparat dalam memahami filosofi perubahan
acara pidana dari inquisatoir ke accusatoir. Perubahan ini menuntut integritas
moral, profesionalisme, dan independensi yang kuat dari penegak hukum dalam
menjalankan tugas.
a. Peradilan Anak Menuju Keadilan Restoratif.
Dalam kajian sistem peradilan pidana anak, Gordon Bazomore
memperkenalkan tiga model peradilan anak, yaitu (a) model pembinaan pelaku
perorangan (individualtreatmentmodel); (b) model retributif; (c) model restoratif.615
Persidangan anak pada model pidana pelaku perorangan dilihat sebagai satu
agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar.
Pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik tentang sebab-sebab
delinkuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut, delinkuensi anak dianggap sebagai
simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta tingkat keseriusannya dilihat tidak
lebih sebagai persoalan terapeutik untuk mengkoreksi dan memperbaiki
gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.
Secara legal formal penerapan keadilan restoratif di Indonesia belum
diatur dalam bentuk undang-undang. Aturan yang jelas mengenai hal tersebut
hanya terdapat dalam SKB tahun 2009 tentang Penangan Anak Yang Berhadapan
615
Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restorative: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang pidato
pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, cet.ke-1, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 26-27.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
285
Dengan Hukum. Penanganan ABH menurut SKB mengenal dua jalur yaitu: jalur
formal dan non formal.616
Dalam ketentuan SKB memerintahkan kepada MA dan
Kejagung untuk menyusun standar operasional prosedur penanganan ABH dengan
pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar
dari model keadilan tradisional yang berpusat pada punishment menuju kepada
keadilan masyarakat (community justice) yang berpusat pada pemulihan korban dan
pelaku. Tidak hanya pada legal justice, tetapi juga mempertimbangkan sosial
justice dan moral justice.617
Pada dasarnya konsep keadilan restoratif terkait dengan konsep diversi dan
diskresi.618
Diversi didefinisikan sebagai bentuk pengalihan proses yang
merupakan program yang hanya dilakukan pada tahap praajudikasi dalam sistem
peradilan pidana. Bentuk pengalihan perkara ini biasanya memang berhubungan
dengan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum. Diskresi
merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan
perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.
Proses diskresi ini berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi
seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu.
Kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 UU No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.619
Terlihat jelas bahwa Polri dalam
616
Paul McCold, The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles, and
Conferencing, dalam Hand book of Restorative Justice: A Global Prespective, 23. Lihat
juga Trisno Raharjo, Mediasi, 33. 617
D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi, 45. 618
Marlina, Pengembangan.., 40. Lihat juga Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan
tentang RUU Pengadilan Anak Tahun 2009, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Depkumham RI, 2009), 49. 619
Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI: Kepolisian adalah segala hal
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
286
kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan
hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga sebagai
garda terdepat penegakan hukum, kepolisian harus diberikan kewenangan untuk
melihat suatu tindak pidana dari sudut pandang yang komperehensif. Oleh karena
itu, diberikanlah kewenangan diskresi dibidang yudisial kepada kepolisian.620
‟„Hal
ini yang kemudian mendorong untuk diaturnya keadilan restoratif dan diversi
dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.‟„
Pendekatan restorative dan asas diversi sebagai roh UU No. 11 tahun 2012
untuk menyelesaikan secara manusiawi kasus hukum anak. Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas diversi menekankan penyelesaian
di luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, bukan lagi
dengan penjara atau hukuman. Sebagaimana tujuan asas diversi diatur Pasal 6 UU
No. 11 tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak,
menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari
perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartipasi, menanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak.Proses hukum terhadap anak, seharusnya dilakukan
melalui pendekatan restorative, dengan tetap berpegang pada undang–undang
yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengambil suatu kebijakan pidana (penal
policy) antara lain; Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak, diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014, Undang-undang
undangan. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI: Fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat. 620
Sebagaimana tertuang pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisan RI:
Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
287
Nomor 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Apabila dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang
peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang
dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai
dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota
United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa
pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi
penerus, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melakukan upaya
hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan
yang disebut dengan peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2014 tentang
pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mengacu
dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa setiap perkara atau
perbuatan pidana anak wajib diberikan perlindungan hukum, dan tidak melihat
dari jumlah ancaman yang timbul dari perbuatan anak.
1). Diversi dan Diskresi Kepolisian Perspektif Keadilan Restoratif.
Sehubungan kewenangan yang dimiliki polisi, maka dalam penanganan
ABH, aparat kepolisian dapat melakukan atau menggunakan kewenangan diskresi
dari pada harus melanjutkan proses hukumnya. Dalam hal ini dikenal dengan
istilah diskresi kepolisian, yang merupakan kewenangan polisi untuk
menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka ataupun
melakukan pengalihan (diversi), dan tujuannya agar anak terhindar dari proses
hukum lebih lanjut. Polisi mempunyai kewenangan diskresi, seperti yang diatur
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
288
dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk
kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Salah satu kewenangan diskresi ini
adalah melalui tindakan diversi dan tentunya tindakan diversi yang dilakukan
tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum bagi aparat
kepolisian melakukan tindakan pengalihan (diversi), sejalan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (3) Konvensi Hak Anak (KHA), yang
menentukan bahwa negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan
pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus
berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan
melanggar hukum pidana dan khususnya:
1. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya
dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
2. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani
anak- anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat
bahwa HAM dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.
Berdasarkan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 (The Beijing Rules),
bagi aparat polisi yang menangani perkara tindak pidana anak juga diberikan
kewenangan untuk melakukan pengalihan. Ketentuannya dapat dilihat pada:
a. Butir 6, disebutkan bahwa:
1. Mengingat kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak
maupun keragaman langkah yang tersedia, ruang lingkup yang
memadai bagi kebebasan anak, untuk membuat keputusan
diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan bagi anak dan pada
tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak,
termasuk dalam penyidikan, penuntutan, pengambilan keputusan
dan pengaturan-pengaturanlanjutannya;
2. Upaya-upaya dilakukan untuk memastikan adanya
pertanggungjawaban yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat
dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan;
3. Mereka yang melaksanakan kebebasan untuk membuat
keputusan, berkualifikasi atau terlatih secara khusus untuk
melaksanakannya secara bijaksana dan sesuai dengan fungsi-
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
289
fungsi serta tugas-tugas mereka.
b. Butir 11, ditegaskan bahwa:
1) Pertimbangan diberikan untuk menangani pelanggar-pelanggar
hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh
pihak berwenang yang berkompeten;
2) Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani
perkara-perkara anak diberikan kuasa untuk memutuskan perkara
demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan
pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang
ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing
dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
peraturan-peraturan ini.
Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-
pelayanan masyarakat atau pelayanan lain, memerlukan persetujuan anak tersebut
atau orang tua walinya, dengan syarat keputusan merujuk pada perkara dan
tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.
Berdasarkan ketentuan ini, maka kepada aparat kepolisian diberikan kewenangan
khusus (diskresi) untuk melakukan pengalihan (diversi) yang menjauhkan ABH
dari proses peradilan formal, penahanan ataupun pemenjaraan. Program diversi ini
dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain adalah dengan
menempatkan ABH di bawah pengawasan badan-badan sosial tertentu guna
membantu anak tersebut memecahkan masalah yang dihadapinya. Secara khusus,
tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar
tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan ABH, tetapi merujuk pada
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, maka penanganan
ABH tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana
formal.
Selain itu, berdasarkan Telegram Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/
XI/2006, tindakan diversi dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian kepada
orang tua si anak, baik tanpa maupun disertai peringatan informal ataupun
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
290
melaksanakan mediasi, seperti menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap ABH
dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatannya.
Penanganan ABH melalui tindakan diversi sebagai upaya untuk mewujudkan
keadilan. Bahwa keadilan adalah suatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat
dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai
perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban
dalam masyarakat.621
Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban,
kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif,
penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta memperhatikan
kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
2). Diversi sebagai Penyembuh bagi Pelaku Anak dan Korban.
Pelaksanaan diversi dalam hal ini hanya dapat dilaksanakan kepada anak
yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana (residive). Hal ini perlu menjadi fokus
perhatian untuk dapat memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua
tahap proses diversi. Anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan untuk
menyetujui program diversi. Pelaksanaan diversi harus mendapatkan persetujuan
korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya,
kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan tindak
pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah
minimum provinsi setempat.
621
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Buku I. (Bandung: Alumni, 2000), 52.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
291
Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelakanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga
menegaskan pemberlakuan diversi terhadap anak yang didakwa dengan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam
bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi
(gabungan). Pelaksanaan diversi ini hanya dapat diberlakukan terhadap anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum
berumur 18 (delapan) belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Namun
demikian, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun tetapi melakukan
atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dapat mengambil keputusan
untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau dapat
mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan
di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang
kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam)
bulan.
Pelaksanaan diversi ini wajib diupayakan pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Penyidik,
penuntut umum dan hakim dalam melakukan proses diversi harus
mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:
1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
292
Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah diversi dan dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
dimulainya diversi. Pelaksanaan diversi melibatkan penegak hukum dalam tiap
proses peradilan (penyidik, penuntut umum, hakim), anak dan/atau orang tua/wali,
korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali,pembimbing kemasyarakatan
serta pekerja sosial profesional. Selain itu, dalam hal dikehendaki oleh anak
dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan
masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping
dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum. Setelah dilaksanakannya
musyawarah diversi maka hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:
1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
2. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan
atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Pelayanan masyarakat.
Hasil kesepakatan diversi ini dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan
Diversi, serta hasil kesepakatan diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan
diversi dibuat. Pelaksanaan diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice apabila
pelaksanaan diversi ini dapat mendorong anak untuk bertanggung jawab atas
perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan
yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan
bagi si korban untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi si
anak untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga serta memberikan
kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan
oleh tindak pidana.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
293
Untuk dapat lebih memaksimalkan penerapan diversi sebagai perwujudan
keadilan restorative, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari para
penegak hukum dalam menangani ABH. Hal ini dapat dilakukan dengan
membentuk tim khusus dalam penanganan ABH dalam setiap tingkatan
pemeriksaan, yang mana tim ini harus diberi pendidikan dan pelatihan sertifikasi
secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan diversi. Pendidikan
dan pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada Hakim Anak yang menangani
perkara tetapi juga diberikan kepada Penyidik serta Penuntut Umum karena proses
diversi wajib dilakukan di tiap tingkatannya. Selain itu juga disarankan agar guru
bimbingan konseling yang ada di sekolah mendapatkan pelatihan khusus terkait
penangangan anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Praktik Restorative Justice Arab Saudi dan Prancis.
Pada bagian ini, kita akan membahas praktik restorative justice pada
Lembaga Pemasyarakatan di dua negara: Arab Saudi dan Perancis. Pemilihan tiga
negara ini berdasarkan pada dua alasan, pertama: kedua negara mewakili dua
sistem hukum yang berbeda: sistem hukum Islam, sistem hukum kontinental.
Kedua, kedua negara yang disebutkan diatas memilki kapasitas untuk mewakili
gagasan yang dikembangkan masing-masing sistem hukum. Arab Saudi
merupakan negara yang dianggap sebagai negara Islam yang paling konsisten
menerapkan hukum pidana Islam yang memiliki konsepsi restorative justice,
Perancis merupakan negara tua yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit
dalam membangun gagasan restorative justice.
A. Praktik Restorative Justice di Arab Saudi.
Arab Saudi adalah negara yang tidak pernah dijajah, namun sebagian dari
wilayahnya, seperti Mekah, Madinah dan Jedah pernah diduduki oleh kekuasaan
Otoman Turki. Namun akhinya ottoman Turki mampu menyingkir pada tahun
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
294
1871 setelah semakin meluasnya pengaruh inggris di Perbatasan Teluk Arab.
Saudi Arabia lahir tahun 1902 dan menjadi Kerajaan Arab saudi sejak 22
September 1933. Berdasarkan Hukum Dasar Arab saudi yang disyahkan oleh
Dekrit Kerajaan, Raja harus patuh dengan syariah (hukum Islam), yang bersandar
pada al-Qur‟an dan Hadist. Arab Saudi merupakan negara Islam yang paling
konsisten dalam menerapkan hukum pidana Islamnya dalam hukum positifnya.
Berbeda dengan sistem hukum kontinental yang berpedoman semata-mata
berdasarkan kehendak pemerintah, parlemen dan badan peradilan. Hukum pidana
Islam utamanya bersandar pada aturan transendental, yaitu al-Quran dan Hadist
serta diskresi hakim. Selain itu dalam prakteknya, hukum pidana Islam juga
berpedoman pada pendapat mahzab,622
terutama empat mahzab utama, yaitu
Maliki, Hambali, Syafi‟i dan Hanafi. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana
Islam, yaitu:
1) Pencegahan dan memberikan efek jera. Penerapan hukum pidana islam
dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku
namun juga bagi mereka yang bermaksud melakukan hal yang serupa.
Selain itu ada kepentingan dan keselamatan masyarakat juga yang
dilindungi dengan penerapan hukuman ini.
2) MerehabilItasi dan Mereformasi.Prinsip taubat (repentance) dikenal dalam
Islam, hal inilah yang medorong konsep rehabilitas dan reformasi
narapidana. Bahwa tindak pidana seberat apapun yang dilakukan, apabila
pelaku bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi, akan mendapatkan
ampunan dari Tuhan. Mengenai hukuman ta’zi >r dan hukuman hadd, Al
Mawardi623
berpendapat: hukuman ta’zi >r dan hukuman hadd adalah untuk
mendisiplinkan, memperbaiki, merehabilitasi.
3) Mencegah, mengeliminasi balas dendam dan rekonsiliasi terhadap korban
atau kerabatnya. Bentuk hukuman dalam Islam sangat bervariatif,
sehingga memungkinkan berbagai macam tujuan dapat dicapai.
622
Empat mazhab yang banyak diikuti umat Islam, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan
Syafii). Lihat: http://www.kamus besar.Com/ 25247/mazhab#nomina. 623
Al Mawardi adalah ahli hukum Islam. Sebagaimana dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh
Islam, jilid 7, (Jakarta: Gema Infsan, 2011), 271.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
295
Dalam hukum pidana Islam, secara garis besar terdapat tiga bentuk
hukuman, yaitu qis}a>s h, hudud, dan ta‟zir. Untuk lebih jelasnya akan dibahas
satu persatu secara singkat:
a. Hukuman qis}a>s}
Qis}a>s dalam arti bahasa berarti tatba‟al atsar pengertian tersebut
digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qis}a>s> mengikuti
dan menelusuri jejak tindak pidana pelaku. Qis}a>s} juga berarti almumatsalatu
yaitu keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian kedua ini diambil
pengertian menurut istilah, yaitu muja>za>tu al-ja>ni> bimitsli fi’lihi > berarti
memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.624
Senada
dengan hal tersebut, Ibrahim Unais memberikan definisi, qis}a>s adalah
menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.
1) Pelaksanaan hukuman qis}a>s dilakukan oleh ahli waris. Tidak ada keutamaan
antara satu ahli waris dengan ahli warisnya, setiap ahli waris memiliki hak yang
sama, tujuannya adalah untuk mengobati rasa duka. Apabila korban tidak
memiliki ahli waris atau ahli warisnya merupakan memiliki agama yang berbeda,
menurut kesepakatan ulama, maka jenis hukuman diserahkan kepada pemerintah
(sulthan), yang akan menentukan hukuman yang paling tepat, qis}a>s h atau
hukuman lainnya seperti pemaafan.
2). Hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan qis}a>s}.
a. Hilangnya objek qis}a>s . Objek qishahs dalam tindak pidana adalah jiwa
(nyawa pelaku), sehingga apabila pelaku meningal dunia maka secara
otomatis pelaksanaan qis}a>s batal.
b. Pengampunan dari Ahli Waris. Pengampunan terhadap qishahs dibolehkan
menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana terdapat dalam ketentuan
Quran Surat Al Maidah 45: barang siapa yang melepaskan (hak
qishahsnya) melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
c. S}ulh (Perdamaian) menurut bahasa berarti Qot }’u al-muna>aza’ah atau yang
memutuskan perselisihan. Apabila dikaitkan dengan qis}a>s , maka
perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian perdamaian antara pihak ahli
624
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), 149.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
296
waris/wali korban dengan pihak pembunuh dalam membebaskan qis}a>s
dengan imbalan. Diyat sebagai Hukuman Pengganti Qis}a>s}.
b. Hukuman Diyat .
Diyat menurut bahasa sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti
kerugian bagi tindakan membunuh atau melukai orang.625
Adapun hal-hal yang
mewajibkan diyat , diantaranya: bila wali atau ahli waris yang terbunuh
memaafkan si pembunuh dari pembalasan jiwa, pembunuhan yang tidak
disengaja, dan pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh. Diyat terbagi
menjadi dua, yaitu diyat ringan dan diyat berat. Diyat ringan untuk
pembunuhan tanpa sengaja, sedangkan berat pembunuhan sengaja tanpa
terencana. Diyat berat adalah 100 ekor unta; 40 ekor diantaranya sedang
mengandung.626
Apabila luka ringan, diselesaikan melalui keputusan yang adil
dari pemerintah (adil), sebagian mengatakan dibayar sebesar biaya pengobatan
dokter. Namun apabila luka yang ditimbulkandiakibatkan perbuatan yang
disengaja, maka diyat nya sebayak 5 ekor unta.627
c. ‘Hukuman Hudu>d’
Hudu>d (merupakan bentuk plural dari had) berarti mencegah, melarang.
Menurut istilah sebuah aturan atau ketetapan Allah yang mengkategorikan sesuatu
sebagai legal atau illegal. Hudu>d merupakan jenis hukuman yang sudah
ditentukan dalam Al-Qur‟an terhadap tujuh jenis tindak pidana (lihat tabel), yaitu:
zina, pencurian, penghinaan, murtad, perampokan, menggunaan alkohol, dan
625
M. Abdul Mujieb, et al, Kamus Istillah fiqh, (PT Pustaka Firdaus: Jakarta), 1994, 61. 626
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Al i‟tishom, 2010), 48. 627
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 57.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
297
pemberontakan. Dalam prakteknya, hakim tidak serta merta menjatuhkan
hukuman apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Apabila terdapat faktor yang
memaafkan, misalnya, hukuman yang semestinya dijatuhkan dapat ditunda. Hal
ini pernah dicontohkan pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab.
d. Hukuman Ta’zi >r
Menurut bahasa ta‟zir artinya menolak. Namun menurut istilah adalah
pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidakmempunyai
hukuman had, qis}a>sh/diyat .628
Ta‟zir mengandung unsur pengajaran, baik yang
diputuskan oleh hakim ataupun yang dilakukan orangtua terhadap anak, dan
seterusnya. Bentuk tindak pidana apa saja yang masuk dalam kategori ta‟zir ini
dapat dikategorikan atau dikualifikasikan oleh perundang-undangan di suatu
negara dan sangat memungkinkan adanya perubahan seiring dengan
perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Bentuk-bentuk hukuman
yang diberikan juga sangat beragam: mulai dari penjara, pengasingan pelaku ke
suatu tempat, perampasan harta, denda, dan sebagainya.
e. Penjara sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman
Hukum pidana Islam memiliki berbagai macam bentuk hukuman. Penjara
hanya merupakan satu dari bagian hukumannya. Keberadaan penjara dimulai pada
saat kekhalifaan Umar bin Khatab (634-644 M), sebagai salah satu bentuk
kebijakan yang dibuatnya. Penjara pertama dibeli di sebuah tempat di Madinah
yang kemudian diikuti oleh para Gubernur ketika itu. Digunakan untuk
menumbuhkan kedisiplinan dan memperbaiki diri pelaku. Masa penahanan
628
M. Abdul Mujieb, et al, Kamus Istillah fiqh.., 384.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
298
beragam tergantung dari berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, mulai dari
satu hari hingga seumur hidup. Namun terdapat perbedaan pandangan dalam
menerapkan lamanya masa penahanan.
B. Praktik Restorative Justice di Perancis
Perancis merupakan negara dengan sistem kontinental yang memiliki
sejarah cukup panjang dalam merintis restorative justice pada sistem peradilan
pidananya, termasuk lembaga pemasyarakatannya. Perancis pernah dikecam oleh
European Human Rights Court (Pengadilan HAM Eropa) karena adanya
penganiayaan dalam Lembaga Pemasyarakatannya.629
Namun, kontribusi Perancis
terhadap dunia dalam membangun sistem peradilan dan pembinaan bagi para
narapidana tetap dapat memberikan inspirasi dalam penerapan restorative justice.
Salah satu bentuk restorative justice yang mendapatkan perhatian khusus di
Perancis adalah pemberian ganti kerugian bagi korban kejahatan. Undang-Undang
17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban mempermudah
pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk
mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua
bulan setelah putusan pengadilan.630
Beberapa hal penting terkait dengan
pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana di Perancis yaitu:
1. Pemberian Ganti Rugi bagi Korban melalui Pengadilan.
Perancis mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban
dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada
korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan
629
Report attacks french‟s human rights record, lihat: http://www.guardian.co.uk/world/2006/feb/
13/france.mainsection. 630
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-v
ctimes -11315.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
299
secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota assosiasi secara
langsung, yaitu contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut
secara langsung anggota assosiasi yaitu contohnya: asosiasi untuk melindungi
binatang. Dalam konteks pembahasan ini, akan difokuskan pada pemberian ganti
kerugian kepada korban individu, yaitu;
1. Syarat pemberian Ganti rugi yaitu: pertama, tindak pidana yang dilakukan
tersebut dapat dihukummenurut hukum perancis. Kedua, tindak
pidana/kejahatan tersebut menyerang kepentingan yang dilindungi oleh
hukum. Ketiga, kerusakan (penderitaan) yang diderita korban memiliki
hubungan yang langsung dengan tindak pidana yang terjadi;631
2. Pihak yang Mengajukan Ganti Kerugian. Pengajuan ganti kerugian oleh
korban dapat diwakilkan oleh ahli warisnya (la reparation de la victim par
richochet) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Perancis (Cour de
Cassation). Pengajuan ganti kerugian oleh ahli waris akan lebih mungkin
diterima apabila telah dimulai terlebih dahulu pengajuan ganti kerugian
oleh korban sebelum meninggal. Adapun pengajuan ganti kerugian yang
bersifat immaterial ditolak oleh Mahkamah Agung Perancis;632
3. Kapasitas Terdakwa. Apabila terdakwa memiliki gangguan psikologis,
terdakwa masih tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap
perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Adapun
terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, Mahkamah
Agung Perancis (sebagaimana dalam sebuah putusan tanggal 9 Mei 1984)
menganggap bahwa mereka tetap bisa dituntut untuk mengganti kerugian
yang diderita korban;
4. Proses Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian. Pada dasarnya korban dapat
mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan pidana atau pengadilan
perdata. Pengajuan gugatan ganti kerugian memiliki masa daluarsa. Untuk
jenis tindak pidana masa daluarsanya setelah 10 tahun terjadinya
kejahatan, adapun untuk tindak pidana ringan selama 3 tahun, dan untuk
pelanggaran selama satu tahun. Pengajuan gugatan prinsipnya diajukan di
Pengadilan tempat kediaman terdakwa atau salah satu dari terdakwa.
2. Restorative Justice di Lembaga Pemasyarakatan Perancis.
Sejarah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Perancis telah berlangsung
sejak abad ke-17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis tahun
1791 menegaskan bahwa penjara adalah tempat untuk memberikan hukuman bagi
631
Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, lihat: http://www
.police.online.fr/lawfr.htm 632
Yvles-Louis Sage, The Operation of the Law of civil Liability in France as am menas of
providing compensatin for persons who suffer loss. Lihat: www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
300
terpidana sekaligus tempat perubahan mereka melalui pekerjaan dan pendidikan.
Selanjutnya, pada tahun 1795 ditentukan pengelolaan penjara berada dibawah
Menteri Dalam Negeri (Ministre de l‟interiuer). Namun sejak tahun 1911,
pengelolaan ini dialihkan ke Menteri Keadilan (Minsitre de la justice).633
Seiring dengan berjalannya waktu, terdapatKomite Percobaan dan
Pertolongan untuk Membebaskan Narapidana (Comite de Probation et
d‟Assistance aux Liberes atau disingkat CPAL) yang dibentuk tahun 1958.
Komite ini lahir sebagai respon atas sangat banyaknya narapidana yang
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan pada umumnya hidup dalam
kondisi yang mengenaskan. Pada tahun 1945 dalam Lembaga Pemasyarakatan
terdapat sekitar 60.000 narapidana.634
Hal ini mendorong Direktur Pelayanan
Lembaga Pemasayarakan ketika itu, Paul Amor, untuk menggagas reformasi
Lembaga Pemasyarakatan. Reformasi Lembaga Pemasyarakatan yang digagas
terdiri dari 14 poin, diantara poin penting tersebut adalah menyiapkan pelepasan
terpidana dengan sistem Release On Parole dan pengawasan paska pemenjaraan
(post-sentence supervision).635
Setelah itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga
pemasyarakatan dan persiapan terpidana untuk dapat hidup ditengah masyarakat
diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan perundang-undangan, seperti:636
1. Pelaksanaan penangguhan hukuman dengan syarat (1959);
2. Pembentukan Pusat Penahanan yang bertujuan untuk pengintegrasian
danPengembangan Hukuman Pengganti (Création des centres de détention
633
Bruno Pellisier dan Yves Perrier, probation in France, 3. lihat: http://www.cepprobation. org/
uploaded_ files/France%281%29.pdf 634
Ibid. 635 http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-0289/histoir
e-de-ladministration-penitentiaire-16945.html 636 http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-0289/histoir
e-de- ladministration-penitentiaire-16945.html
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
301
orientés vers la réinsertion et le développement des peines de substitution)
tahun 1975;
3. Pembentukan Hukuman Kerja Sosial dan Reformasi Hak-Hak Narapidana
tahun 1983;
4. Reformasi Perawatan Kesehatan bagi tahanan tahun 1994;
5. Pembentukan Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dan Percobaan tahun
1999;
6. Undang-Undang Tentang Orientasi dan Program Untuk Keadilan:
Peningkatan Keamanan dan Kemanusiaan Bangunan Lembaga
Pemasyarakatan tahun 2002 (loi d'orientation et de programmation pour
la justice: sécurisation et humanisation renforcées des établissements
pénitentiaires);
7. Undang-Undang yang mendukung perwujudan keadilan terhadap
perubahan kriminalitas melalui pengaturan hukuman untuk memberantas
tindakan residivis (la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité développe les aménagements de peine pour lutter contre la
récidive) tahun 2004;
8. Pengesahan Piagam Aksi Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (la
charte d'action de l'administration pénitentiaire) Tahun 2007;
9. Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru tahun 2009 (la loi
pénitentiaire) tanggal 24 November 2009.
Pasal 1 Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan tanggal 24 November
2009 menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki
beberapa tujuan sekaligus yaitu: melindungi masyarakat, memberikan sanksi bagi
terpidana, menjaga kepentingan korban dan mempersiapkan narapidana tersebut
untuk dapat berintegrasi dengam masyarakat setelah keluar dari penjara.637
Salah
satu tujuan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah agar dapat
berintegrasi dengan masyarakat selepas menjalani hukumannya. Untuk mencapai
tujuan ini, salah satu hal yang dipersiapkan adalah memfasilitasi kebutuhan
narapidana di penjara dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka tetap
dapat hidup dan menghidupi diri dan keluarganya selepas ditahan.
637
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
302
3. Release On Parole sebagai Gagasan Perancis.
Tidak semua narapidana harus menjalankan masa tahanannya hingga
selesai. Sebagian dari mereka mendapatkan dispensasi sehingga dapat keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan sebelum waktunya. Dalam konteks ini, Perancis
memiliki jasa dalam merintis kebijakan ini sehingga diadopsi di banyak negara.
Parole berasal dari bahasa perancis yang artinya kata, yang digunakan terkait
dengan bebasnya tahanan. Terdapat gagasan bahwa bebasnya mereka atas dasar
kata-kata terhormat mereka, bahwa mereka tidak akan mengulangi kejahatannya.
Hal ini telah dipraktikkan sejak abad ke 18 yang membolehkan narapidana untuk
dibebaskan sebelum menjalani masa hukumannya secara penuh.638
Menurut kamus hukum, release on parole:639
the release of a convicted
criminal defendant after he/she has completed part of his/her prison
sentence, based on the concept that during the period of parole, the released
criminal can prove he/she is rehabilitated and can "make good" in society.
A parole generally has a specific period and terms such as reporting to a
parole officer, not associating with other ex-convicts, and staying out of
trouble. Violation of the terms may result in revocation of parole and a
return to prison to complete his/her sentence.
Jadi release on parole adalah pembebasan terpidana setelah narapidana
tersebut menjalani sebagian masa hukumannya dengan syarat. Berlandaskan
pada konsepsi bahwa pada masa periodepembebasan (on Parole) yang
bersangkutan dapat membuktikan dirinya telah berubah dan dapat menjadi
anggota masyarakat yang baik. Terhadap pelangaran ini maka pembebasan
ini akan dicabut dan yang bersangkutan akan dkembalikan ke Lembaga
Pemasyarakatan.
Release on parole berakar dari Perancis sejak abad ke-18. Gagasan release
on parole datang dari seorang hakim yang bernama Arnauld Bonneville yang
mengenalkan dan mensistematiskan ide tentang pembebasan bersyarat
(conditional liberation) selama pertengahan abad ke-19. Tahun 1846 Hakim
Bonneville memaparkan idenya di depan Parlemen Perancis tentang konsepsi
638
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444506/parole 639
http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1451
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
303
pembebasan bersyarat, bagi mereka yang telah menjalani hukuman setengah dari
yang semestinya. Setelah terpidana menyampaikan bukti-bukti yang tak
terbantahkan kalau narapidana tersebut layak untuk keluar sebelum waktunya,
maka terpidana diijinkan untuk dibebaskan setelah bersedia pula mematuhi syarat-
syarat yang ditetapkan sebelum pembebasannya.
Terdapat empat hal yang menjadi point penting gagasan Hakim
Bonnevile640
terkait dengan rehabilitasi korban dan perlindungan masyarakat pada
saat bersamaan, yaitu: pertama, memotivasi terpidana untuk merubah hidupnya
sebelum keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kedua, perlindungan dan dukungan
fisik dan psikologis bagi terpidana dan keluarganya selama periode pembebasan
bersyarat. Ketiga, pemantauan dan pengawasan selama periode pembebasan
bersyarat. Keempat, penghukuman kembali (kembali ke Lembaga
Pemasyarakatan) ketika ada perilaku yang buruk atau pelanggaran terhadap
syarat-syarat yang ditetapkan selama periode pembebasan bersyarat.
Walaupun beranjak dari sistem hukum yang berbeda, terdapat benang
merah dari praktik restorative justice pada kedua negara: bahwa keduanya
berupaya untuk memenuhi tujuan yang sama melalui pemberian hukuman atas
perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang: yaitu memenuhi
keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan
serupa dan dapat diterima masyarakat, melindungi masyarakat, memkompensasi
kehilangan yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam konteks pemberian
hukuman berupa pemenjaraan, Lembaga Pemasyarakatan dirancang sedemikian
rupa agar dapat memenuhi kebutuhan narapidana sehingga pada saat terpidana
640
Christopher L., "Conditional Liberation (Parole) in France" (1978). Scholarly Works.Paper 315.
lihat: http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1336&context=facpub
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
304
menyelesaikan masa tahanannya, dia dapat siap tinggal dan hidup di tengah
masyarakat. Hal yang perlu dilakukan adalah sebagaimana praktek di Perancis,
negara harus dapat melakukan reformasi dalam berbagai aspek, seperti
mempermudah ruang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas
kerugian yang diderita sehingga hubungan korban dan terpidana tereparasi,
memfasilitasi narapidana untuk beraktualisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan
khususnya sesuatu yang bersifat produktif dan dapat dikomersilkan, pembenahan
administrasi Lembaga Pemasyarakatan, perawatan kesehatan bagi terpidana, dan
pemenuhan hak-hak narapidana seperti memfasilitasi kebutuhan narapidana
bersama istri/suaminya sebagiamana yang dilakukan di Arab Saudi.
Selain perbaikan terhadap hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan,
praktik yang dijalankan di Selandia Baru dan Arab Saudi melalui implementasi
hukuman lain selain pemenjaraan, yaitu hukuman yang berbasis masyarakat
(community based sentences) dan bentuk hukuman lain seperti diyat (membayar
denda), perampasan aset, hukuman cambuk merupakan berbagai jenis hukuman
alternatif yang dapat dipelajari implementasinya di Indonesia. Berbagai jenis
hukuman tersebut, pada hakikatnya dapat mengurangi beban negara terutama
secara finansial tanpa secara bersamaan mengurangi hakikat tujuan pemidanaan
sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Namun begitu pelaksanaan terhadap hukuman pengganti tersebut perlu
persiapan yang memadai. Bukan hanya pengelolaan manajemen Lembaga
Pemasyarakatan yang sudah baik, perlunya pembentukan lembaga-lembaga
pendukung (semacam Community Probation Service), namun juga perlunya
dukungan yang besar darimasyarakat, misalnya melalui lembaga-lembaga
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
305
(perkumpulan masyarakat) yang dapat menerima keberadaan narapidana di
tengah-tengah mereka.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
306
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah meneliti dan mencermati dinamika perkembangan restorative
justice dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan
hubungannya dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia, penulis
menyimpulkan bahwa:
1. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam dikenal dengan istilah
al- afwu dan s}ulh, memberikan kesempatan dan kemungkinan bagi korban
kejahatan untuk memperoleh reparasi dan rasa aman, pelaku dapat
memahami sebab dan akibat perbuatannya dan bertanggung jawab dengan
cara yang berarti, serta masyarakat dapat memahami sebab utama
terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencegah kejahatan. Perbuatan memaafkan dan perdamaian dari
korban‟„atau keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak
pelaku bisa dijatuhi sanksi diyat (yaitu sejumlah harta tertentu untuk
korban dan keluarganya). Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi
yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses
peradilan pidana.
2. Hukum Islam merupakan Living laws di Indonesia. Hukum Islam bisa
dipakai sebagai bahan atau sumber hukum bagi pembaruan hokum pidana
nasional. Hukum pidana Islam sangat menganjurkan penyelesaian perkara
pidana dengan cara perdamaian. Terdapat perbedaan yang sangat besar
antara penyelesaian perkara pidana menurut hukum pidana Islam dan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
307
hukum pidana nasional tentang Restorative Justice mengenai tindak-tindak
pidana yang dapat dilaksanakan pemaafan dan perdamaian, ini bisa
menjadi komparasi untuk sistem peradilan pidana yang berada di
Indonesia. Sehingga semangat untuk menyelesaikan permasalahan dengan
pemaafan dan perdamaian bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh
rakyat Indonesia.
3. Konstruksi pendekatan restoratif hukum pidana Islam dilakukan dengan
mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam kedalam hukum pidana
nasional. Hukum pidana nasional tidak harus sama persis dengan hukum
piana Islam, melainkan hukum pidana Islam menjiwai produk pembaruan
hukum pidana nasional. Dengan metode za>wa>jir dan pendekatan ta’aqquli >,
maka diharapkan proses pembaruan hukum pidana nasional bisa
memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum, serta lebih
mudah diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
B. Implikasi Teoritik
Disertasi ini berusaha untuk menampilkan teori yang pas dan cocok untuk
digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan dan merancang pembaruan
hukum pidana Indonesia. Proses pembaruan hukum pidana Indonesia tidak bisa
dilakukan hanya melalui satu pendekatan, karena kompleksitas problem yang
dihadapi, mulai dari perbedaan agama, ras, suku bangsa, Bahasa, adat istiadat dan
lainnya. Oleh karena itu, disertasi ini menawarkan beberapa pendekatan yaitu;
Teori dekonstruksinya an-Naiem dan teori Zawajir-nya Ibrahim Hosen.
Dalam melakukan pembaruan teori hukum publik Islam, An-Na‟im
menawarkan teori naskh atau teori “naskh terbalik”. Teori ini sejatinya
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
308
merupakan bentuk upaya rekonstruksi dari metode nasakh yang sudah mapan
dalam kajian ushūl al-fiqh. Pendekatan rekonstruktif ini, An-Na‟im tempuh dalam
rangka menyesuaikan nash-nash Alqur‟an dan al-Sunnah dengan kondisi modern.
Hal ini dilakukan guna memenuhi tuntutan penerapan al-Qur‟an dan al-Sunnah.
Karenanya, perlu interpretasi yang memadai agar semangat yang dikandungnya
dapat ditangkap.
Teori berikutnya diambil dari Ibrahim Hossen, seorang pemikir Hukum
Islam dari Indonesia. Terkait pembaruan hukum pidana Islam, Ia menawarkan
pendekatan zawājir; yakni hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap
pelaku tindak pidana tidak harus persis atau sama bentuk hukumannya dengan apa
yang secara tekstual termaktub dalam Alqur‟an dan al-Hadits. Pelaku boleh
dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut
mampu mencapai tujuan hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa
takut bagi orang lain untuk melakukan tindakan pidana. Dalam rumusan
ijtihadnya pada bidang hukum pidana Islam, Ibrahim Hosen menggunakan
pendekatan ta‟aqqulī dari pada pendekatan ta‟abbudi> (hukum Islam diterima apa
adanya tanpa disertai komentar (rasionalisasi). Pendekatan ta‟aqqulī lebih
menekankan rasionalisasi ajaran dalam hokum pidana Islam agar mudah dipahami
dan dapat dilaksanakan secara simultan dalam teori dan praktiknya secara
bersamaan.
Restorative Justice dalam hukum pidana Islam dapat berimplikasi pada
efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan akan berkurang, penjara
tidak akan over capacity serta terciptanya keamanan dan ketentraman dalam
masyarakat.Hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
309
hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penyerapan nilai-nilai hukum
pidana Islam dapat terlaksana dengan baik melalui proses objektifikasi istilah-
istilah teknis dan bentuk-bentuk hukuman dari hukum pidana Islam. Dengan
metode ini, diharapkan hukum pidana Islam secara subtansial-kontekstual tetap
menjadi bagian dari jiwa pembaruan hukum pidana Indonesia, meskipun secara
formal-tekstual tidak nampak di permukaan, sesuai dengan kaidah, “Ma laa
yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu” (sesuatu yang tidak mungkin terwujud
seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan (yang terpenting didalamnya) seluruhnya”.
C. Keterbatasan Penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini dari awal hingga hasil akhir penelitian,
tentu terdapat banyak sekali kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan yang
penulis rasakan, antara lain:
Pertama, lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini hanya terfokus pada
studi kepustakaan dan sejarah saja, yaitu berupa kajian literature dan pemikiran
para tokoh. Namun, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau perbandingan
bagi akademisi, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat, mengingat
pentingnya konsep restoratif ini.
Kedua, penelitian pembanding dan lanjutan. Jika ditelisik lebih dalam,
penelitian tentang restorative justice perspektif filsafat hukum Islam belum
banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, sehingga penelitian ini bersifat
temuan baru dan bisa dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lainnya.
Ketiga, penelitian tentang restorative justice perspektif filsafat hukum
Islam ini belum komprehensip. Maka perlu pemetaan secara historis, sehingga ada
kajian historis yang representative yang dapat menggambarkan proses masuknya
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
310
nilai-nilai hukum pidana islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia,
khususnya nilai-nilai restorative justice dalam hukum pidana Islam.
D. Rekomendasi.
Konsep restorative justice belum diatur secara jelas dalam sistem
peradilan pidana kita sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang
sulit dan dilematis mengingat penyelesaian perkara dalam perkara pidana kita
sangat formalistik legalistik. Konsep ini harus diberi payung/kerangka hukum
yang dintegerasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana
formil (KUHAP). Agar konsep ini dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana ringan, harta kekayaan dan badan serta jiwa, maka seyogyanya
konsep ini dirumuskan dalam suatu perundang-undangan nasional. Hal itu
diperlukan karena tanpa suatu undang-undang yang mengatur secara tegas konsep
restorative justice atau perdamaian, maka aparat penegak hukum akan
menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Politik hukum dalam kebijakan
legislasi mengenai restorative justice merupakan jawaban atau solusi untuk
mengatasi masalah yang timbul dalam praktek yang diakibatkan bekerjanya
sistem peradilan pidana. Oleh karena itu adanya payung hokum diperlukan agar
restorative justice memperoleh akar yang lebih kuat dalam implementasinya,
sehingga mengembalikan tujuan hukum pidana sebagai ultimum remedium.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
311
Daftar Kepustakaan
Abdullah, M. Amin, Preliminary Remarks on The Philoshophy of Islamic
Religious Science dalam al-Jami‟ah: Journal of Islamic Studies No. 61
tahun 1998.
Abdullah, Musthafa. dkk. Intisari Hukum Pidana, (Jakarta; Ghalia Indonesia,
1983).
Abi> Sulaima>n, Abd al-Wahha>b Ibra>hi>m, al-Fikru al-Us}u>li> : Dira>sah Tahli>liyyah Naqdiyyah, Jeddah: Da>r al-Syuru>q,1983.
Aertsen, Ivo. et.al, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the
Concept of Empowerment, (Journal TEMIDA, Mart 2011).
al-Ghaza>li>, Abu> Ha>mid. al-Mustasyfa> min Ilm al-Us}u>l, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.,
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-11,2004).
Al-Qat}t}a>n, Manna>’. Maba>hist fi> Ulu>m al-Qur’a>n, t.tp, Mansyu>ra>t al-As}r al-
Hadits>, t.th.
Amal, Taufik Adnan, Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran
Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1994.
An-Na‟im, Abdullahi Ahmed. Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa
Depan Syari‟ah, terj. Sri Murniati Bandung: Mizan, 1997.
An-Na‟im, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties,
Human Rights and International Law New York: Syracuse University
Press, 1996.
Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM. Books,
2007).
Arief, Barda Nawawi. 2010, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar
Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010).
Ash-Shidiqie, Tengku Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Semarang:
PT. Pustaka Rizki Mulia, 2001.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
312
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System):
Perspektif Eksisten sialisme dan Abolisionisme, Bandung; Bina Cipta.
1996.
‘Audah, Jasser. Maqa>s}id al- Shari>’ah Falsafah Li al-Tashri >’ al-Isla>mi> (London:
The International Institute Of Islamic Thought, 2007).
Audah, Jasser. Maqasid As Philoshophy Of Islamic Law (London: The
International Institute Of Islamic Thought, 2008).
Audah, Abd al-Qadir al-Tasyri> al-Jina>’i > al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wadh’i >, Jilid I, (Beiru>t: Muasasah al-Risa>lah Litiba >’ah wa al-Nasyr wa al-
Tauzi>’i, 1992).
Azhari, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode
Negara Madinah dan Masa Kini, cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010.
Azizy, Qodri Abdillah. Membangun Integritas Bangsa, (Jakarta: Renaisan, 2004).
Azizy, A. Qodri A. Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum
Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Bruinessan, Martin Van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Bandung: Mizan,
1995.
Burdah, Ibnu (ed.), Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan
Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara Wacana,
2008.
Dahlan, Mohammad,Abdullah Ahmed An-Naim: Epistimologi Hukum Islam, cet.
ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Djazuli, A. Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu syariat.
Jakarta: Predana Media. 2003.
Djazuli, Ahmad, Ilmu fiqh; Penggalian dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta:
Kencana, 2010.
Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik
Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina,1998.
Fanani, Muhyar, Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai
Cara Pandang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
H. Strang, J. Braitwaite (eds), Restorative Justice: Philosophy to Practice.
Journal TEMIDA Mart 2011.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
313
Hamzami, Achmad Irwan. Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan
Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qis}a>s -Diyat dalam
Hukum Pidana Islam, Semarang: PPs. Universitas Diponegoro, Desertasi,
2015.
Hosen, Ibrahim, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Putra Harapan,
1990.
Ibrahim, Duski, Metode Penetapan Hukum Islam;Membongkar Konsep al-Istiqra‟
al-Ma‟nawi al-Syathibi Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, Panduan Hukum Islam, alih bahasa Asep Saefullah
FM dan Kamaluddin Sa‟adiyat uharamain, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka
Azam, 2007.
Juhaya S. Praja. Filsafat Hukum Islam. Dalam Tjun Surjaman (ed.). Hukum Islam
di Indonesia: Pemikiran dan Praktik, Bandung: Remaja Rosdakarya.,1991.
Katsir, I. Tafsir Ibnu Katsir. (A. Ghoffar & M. Abdul, Trans.). Bogor: Pustaka
Imam asy Syafi‟I, 2003.
Khalla>f, Abd al-Wahha>b. Ilm Us}u>l al-Fiqh. Al-Qa>hirah: Da>r al-‘Ilm‘li al-
Thiba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tawz>i’, 1978.
Khallaf, Abdul Wahhab, Sumber-Sumber Hukum Islam, alih bahasa Bahrun Abu
Bakar, cet. ke-1, Bandung: Risalah, 1984.
Levin, Marc. Restorative justice in Texas: Past, Present and Future, Texas: Texas
Public Policy Foundation, 2005.
M. Sularno, Syari‟at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia,
dalamJurnal al-Mawardi, Edisi XVI, 2006.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari‟ah,,Jurnal Hukum,
No. 1 Vol. 14, Januari 2007.
Mathew Lipman et all, Islamic Criminal Law and Procedure, New York: Praeger,
1988.
Mawardi, Imam al-, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-
3, Jakarta: Darul Falah, 2007.
Mohammad Daud Ali. Kedudukan Hukum Islam dal am Sistem Hukum
Indonesia, Dalam Taufik Abdullah dan sharon Siddiq ue (ed.). Tradisi dan
Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan.
Jakarta: LP3ES, 1989.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
314
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2001).
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung:
Alumni, 1992.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana,
Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Islam, Jakarta: Sinar
Grafika, 2004.
Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial,Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1991.
Nazir, Moh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Nu‟mani, S. M. S. Serial Lelaki yang Dijamin Masuk Surga, Best Stories of Umar
bin Khaththab. (A. Aziz, Trans.). Jakarta: Kaysa Media. 2015.
O‟ Connell, & Morris and Max-well, Restorative or Community Conferencing,
The IIRP, 2001.
Poerwandari, E. Kristi. Pendekatan Kualitatif Untuk Perilaku Manusia, 3rd
ed.
Jakarta: LPSP3, 2009.
Praja, Juhaya S., Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
R. Bogdan dan Steven Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods,
John Wiley & Sons, 1984.
Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif, Equilibrium 5, no. 9, 2009.
Ritzer, Goerge, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta:
Penerbit CV. Rajawali, 1985.
Rofiq, Ahmad. Kritik Metodologi Hukum Islam Indonesia, dalam Anang Haris
Himawan (ed.) dalam Epistemologi Syara‟ Semarang: IAIN Walisongo
Press, 1998.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. (K. A. Marzuki, Trans.). Bandung: Al-Ma‟arif.1987.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Alma‟arif,
1995, 12 Jilid.
Safi, Louay, Ancangan Metodologi Alternatif (The Fondation ofKnowledge; A
Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, terj. Imam
Khoiri Yogyakarta: TiaraWacana, 2001.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
315
Shihab, M. Q. Tafsir Al-Mishbah Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Quran.
Jakarta: Lenteng Hati.2000.
Sjadzali, Munawwir, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997.
Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.2010.
Sudarto. Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto. 2013.
Summa, Muhammad Amin dkk, Pidana Islamdi Indonesia; Peluang, Prospek dan
Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus,2001.
Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Pres,
2005.
Sutrisno, Fazlur Rahman; Kajian Kritis terhadap Metode, Epistemologi dan
sistem Pendidikan, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006.
Syahrur, Muhammad, al-Kitāb wa al-Qur’ān, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba’ah
wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1992.
Syahrur, Muhammad, al-Kita>b wa al-qur’a>n; Qira>‟ah Mu‟a>s}irah, Damaskus: al-
Ahali, 1990.
Syahrur, Muhammad, Dira>sah Islāmiyyah, Mu’a>s}irah Damaskus: al-Ahali li al-
Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, cet. 1, 1994.
Syalt}u>t, Mahmu>d. al-Isla>m Aqi>dah wa as-Syari>’ah. Kairo: Da>r al-Qalam. Cet.
III.1966.
Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006.
Tamrin, Dahlan, Filsafat Hukum Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007.
Tanya, Bernard T. dkk.,Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. IX.1997.
Turner, Jonathan H. The Structure of Sociological Theory,Homewood Illinois:
The Dorsey Press, 1975.
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam, jilid 7, Jakarta: Gema Infsan, 2011.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
316
Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi
Sosial dan Perilaku Sosial, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas)Tahun.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang
Permberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
317
Laporan Penelitian/Makalah:
Mudzakir. Viktimologi Studi Kasus di Indonesia, Makalah, disampaikan pada
Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-XI, Surabaya.2005.
Rena Yulia Nuryani. Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal, Universitas
Islam Bandung, Bandung.2009.
Taufik Hidayat, Restorative Justice Sebuah Alternatif, dalam Jurnal Restorasi,
Edisi IV, Volume 1. 2005.
Jurnal
Diana, Rika. Kekerasan dalam Rumah Tangga, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor
1/71-84.
Fox, Darrell. Social Welfare and Restorative Justice, Journal Kriminologija
Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68,
(London Metropolitan University: Department of Applied Social Sciences,
2009).
Kryger, Martin. Law as Tradition, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2
August 1986.
Mudzakir. Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana, Makalah disampaikan
pada‟“Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas
Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia
(MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
Mulyadi, Lilik. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:
Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik, Yustitia Edisi 85 Januari-
April. 2013.
Prayitno, Kuat Puji. Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12. 2012.
Rahman, Fazlur, Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives, dalam
International Journals of Middle East Studies, Vol. I, tahnun 1970.
Rahman, Fazlur, The Concept of Hadd in Islamic Law, dalam Islamic Studies
Journal, Vol. IV, No. 3 September 1965.
Saloko, Murniati. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus. 2011.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
318
Website
Admin (Ed), Hukum Progresif: Belajar dari Kasus Sudarta, http://harnas.
co/2014/ 12/22/belajar-dari-kasus-sudarta, diakses tanggal 05 Oktober
2020.
Christopher L. Conditional Liberation (Parole) in France, (1978). Scholarly Works.
Paper 315. lihat: http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=
1336&context=facpub.
http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs.html.
Ettienne verges, procedure penale, Litec: Paris, 2005.
http://152.118.58.226 - Powered by Mambo Open Source Generated; 2019/02 /21.
http://books.google.co.id, Keadilan yang lebih mendekatkan diri dan mendengar
jeritan korban.
http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1451.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444506/parole://www.corrections.govt.z/
http://www.corrections.govt.nz/about-us/corrections-vision.html
http://www.corrections.govt.nz/careers/opportunities-at-corrections/cpps-jobs/probation-
officer.html.
http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-thecommunity/int
roduction.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/
http://www.menulisproposal.penelitian.compendekatanfenomenologidalam.html.
(2019/12/21).
http://www.paroleboard.govt.nz/about-us/cases-and-eligibilit. html. http://www.parole
board.govt.nz/utility/privacy-statement.html
https//id.m.wikipedia.org.Program Legislasi Nasional 2015-2019, (2019/02/21).
Jacques Borricand, World Factbook of Criminal Justice System in France, lihat:
http://www.police.online.fr/lawfr.htm.
Medan Bisnis, Mahkamah Agung: UU KDRT Berkiblat ke Asing,http://www.
medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/22/137020/mahkamah-agung-
uu-kdrt-berkiblat-ke-asing/#.VMkqfXufhVc, 05 Oktober 2020.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
319
Poernomo Gontha Ridho. Indonesia Bisa Terapkan Sanksi Pidana Tanpa Penjara,
http://www.infoanda.com., diakses tanggal 29 Oktober 2020.
Report attacks french‟s human rights record, lihat: http://www.guardian.co.uk/
world/ 2006/feb/13/france.mainsection.
Widodo. Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia: Urgensi dan Implikasinya. http://id.portalgaruda.org. diakses
pada tanggal 5 Oktober 2020.
Wikipedia,the free encyclopediahttp://en.wiki-pedia.org/wiki/Restorative justice;
(2019/02/21).
www.kompas.com. Keadilan prosedural, (2019/02/21).
www.suaramerdeka.com. Keadilan prosedural, (2019/02/21).
Yvles-Louis Sage, The Operation of the Law of civil Liability in France as am
menas of providing compensatin for persons who suffer loss. www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc