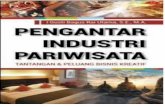Dampak Industrialisasi Pariwisata Terhadap Kemiskinan Masyarakat Pesisir
Transcript of Dampak Industrialisasi Pariwisata Terhadap Kemiskinan Masyarakat Pesisir
DAMPAK INDUSTRIALISASI PARIWISATATERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR
Sokemd Arjunaroi ManullangProgram Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik,Universitas Jember
ABSTRAK
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahpenduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa.Sebagian besar jumlah penduduk miskin tersebut merupakanmasyarakat pesisir. Kemiskinan masyarakat pesisir banyakdipengaruhi oleh aspek lingkungan, keragaman potensi sumberdaya ekonomi lokal, peluang pasar, akses permodalan dankualitas sumber daya masyarakat pesisir. Permasalahan inimenjadi masalah nasional, mengingat negara kita adalah negaramaritim yang 70% wilayahnya terdiri dari lautan.
Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yangpenanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadiprioritas utama dalam program-program pemerintah. KementerianKelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah melakukanprogram pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan danPerikanan (PNPM Mandiri KP), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), danPengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Serta pembentukankelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat pesisir sepertiKelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP), KelompokPembudidaya Ikan (PokDaKan), Kelompok Pengolah Pemasar(PokLahSar), Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), dan KelompokMasyarakat Pesisir (KMP). Semua program-program pemerintah inimenjadi usaha menyelesaikan permasalahan nasional, yaitukemiskinan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri jugamemiliki program pemberdayaan masyarakat terhadap potensidaerah wisata. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat terutama masyarakat miskin melaluipengembangan desa wisata. Yang dimaksud desa wisata (Muliawan,
2008) adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya dayatarik wisata yang khas, desa yang dikelola dan dikemas secaramenarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukungwisatanya, serta desa yang mampu mengerakkan aktifitas ekonomipariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan danpemberdayaan masyarakat setempat. Dengan potensi wilayahkelautannya yang luas, Indonesia memiliki banyak obyek wisatalaut yang menarik dan unik. Beberapa obyek wisata yang bisadisebutkan, antara lain Danau Toba Sumatera Utara, PulauSeribu, Karimun Jawa, Wisata Bahari Lamongan, Pantai KutaBali, Pantai Derawan Kalimantan Timur, Taman Laut BunakenSulawesi Utara, Raja Ampat Papua, dan masih banyak lagi.Obyek-obyek wisata laut ini bukan saja dikenal di kalanganwisatawan domestik, tetapi sudah menjadi daya tarik wisatawanmancanegara untuk menikmati keindahan alam Indonesia.
Banyaknya obyek wisata laut di Indonesia diharapkanmenjadi salah satu indikator pendorong pemberdayaan masyarakatpesisir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Makalah iniakan membahas dampak industrialisasi pariwisata terhadapkemiskinan masyarakat pesisir. Dengan cita-cita pengentasankemiskinan nasional, diharapkan makalah ini menemukan hubunganantara industrialisasi pariwisata dan kemiskinan masyarakatpesisir.Kata kunci: pariwisata, kemiskinan, masyarakat pesisir.
1
PENDAHULUAN
Secara geografis Indonesia merupakan negara yang menganut
prinsip-prinsip negara kepulauan dan negara kemaritiman.
Prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) Indonesia dicetuskan
pertama kali pada Deklarasi Djuanda1 yang menyatakan bahwa
Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan wilayah yang
terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan dan
menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Negara Indonesia juga merupakan negara
kelautan (negara maritim) karena memiliki luas wilayah
perairan2 3.350.483 Km2 dan memiliki garis pantai terpanjang
kedua di dunia yang mencapai kurang lebih 81.000 Km. Kondisi
geografis Indonesia tersebut menjadi sumber daya alam yang
memiliki potensi ekonomi untuk dikelolah bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 33. Potensi ekonomi perairan Indonesia terdapat dalam
perikanan, produksi garam, pengolahan kekayaan laut seperti
terumbu karang dan rumput laut, serta kondisi alam sebagai
obyek pariwisata. Potensi-potensi ekonomi ini terdapat
diseluruh wilayah perairan Indonesia, dikelolah oleh
pemerintah maupun oleh pihak swasta serta dimanfaatkan oleh
masyarakat sekitar daerah perairan untuk memenuhi kebutuhan
hidup.
Sepanjang garis pantai Indonesia terdapat masyarakat yang
bergantung secara langsung pada sumber daya laut yang1 Dicetuskan tanggal 13 Desember 1957 dan tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara.2 Wilayah daratan berair dan wilayah lautan.
2
diperkirakan Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki potensi
ekonomi 1,2 triliun Dolas AS pertahun. Sedangkan, berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada
Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa, yang sebagian besar
jumlah penduduk miskin tersebut merupakan masyarakat pesisir.
Fakta tersebut menjadi fenomena sosial-ekonomi yang
menyedihkan, di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam,
khususnya kekayaan alam di perairan, banyak penduduk Indonesia
yang masih miskin. Kemiskinan masyarakat pesisir ini banyak
dipengaruhi oleh aspek lingkungan, keragaman potensi sumber
daya ekonomi lokal, peluang pasar, akses permodalan dan
kualitas sumber daya masyarakat pesisir. Upaya pengentasan
kemiskinan masyarakat pesisir ini menjadi pokok permasalahan
yang harus segera diatasi dan menjadi pokok tujuan dari
berbagai program kinerja pemerintah. Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia telah melakukan program
pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM
Mandiri KP), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP),
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa
Pesisir Tangguh (PDPT). Serta pembentukan kelompok-kelompok
pemberdayaan masyarakat pesisir seperti Kelompok Usaha
Kelautan dan Perikanan (KUKP), Kelompok Pembudidaya Ikan
(PokDaKan), Kelompok Pengolah Pemasar (PokLahSar), Kelompok
Usaha Garam Rakyat (KUGAR), dan Kelompok Masyarakat Pesisir
(KMP). Semua program-program pemerintah ini bertujuan untuk
mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir.
3
Mayoritas mata pencaharian masyarakat pesisir adalah
nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan dipercayai memiliki nilai-
nilai luhur yang tinggi. Nelayan adalah pekerjaan yang
bergantung pada kondisi alam dan sumber daya ikan yang ada,
artinya nelayan mempercayai kehidupannya bergantung pada
berkah yang diberikan oleh Tuhan. Budaya ritual petik laut
atau sedekah laut atau larung saji yang dilakukan nelayan
merupakan bentuk ucapan syukur dan doa kepada Tuhan agar
memberkahi dengan kelimpahan kakayaan laut dan keselamatan
nelayan ketika menangkap ikan. Selain nelayan, masyarakat
pesisir bekerja di sektor nonperikanan seperti pemasaran ikan
laut, usaha produksi garam, produksi pengolahan rumput laut,
kerajinan tangan dari benda-benda laut, dan pekerjaan di
sektor-sektor lain. Variasi pekerjaan masyarakat pesisir ini
perlu dikembangkan agar tidak tergantung sepenuhnya terhadap
pekerjaan nelayan. Ketergantungan penghasilan dari pekerjaan
nelayan akan menimbulkan masalah ekonomi keluarga nelayan
ketika musim paceklik. Pada musim paceklik dan kemarau panjang
nelayan sulit menangkap ikan. Pada musim tersebut nelayan
beralih pekerjaan sesuai keahlian lain yang dimiliki.
Wilayah perairan tidak hanya memiliki potensi ekonomi pada
peluang usaha sektor perikanan dan usaha sektor nonperikanan,
tetapi juga pada pemanfaatan kondisi alam wilayah perairan
menjadi obyek wisata. Daerah pantai merupakan tujuan wisata
yang paling digemari wisatawan pada umumnya. Faktor pendorong
yang menjadikan daerah pantai sebagai obyek wisata antara lain
keindahan pemandangan alam, biaya yang terjangkau, suasana
yang aman dan nyaman untuk bersantai atau bermain air,
4
menikmati masakan dan minuman khas daerah wisata, dan daya
tarik kebudayaan masyarakat setempat. Beberapa obyek wisata
yang bisa disebutkan, antara lain Danau Toba di Sumatera
Utara, Pulau Seribu di Jakarta, Karimun Jawa di Jawa Tengah,
Wisata Bahari Lamongan di Jawa Timur, Pantai Kuta dan Pantai
Sanur di Bali, Pantai Derawan di Kalimantan Timur, Taman Laut
Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua, dan masih
banyak lagi. Obyek-obyek wisata laut ini bukan saja dikenal di
kalangan wisatawan domestik, tetapi sudah menjadi daya tarik
wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan alam
Indonesia.
Pariwisata adalah pembangunan ekonomi yang melibatkan
secara langsung masyarakat setempat. Pembangunan pariwisata di
daerah pesisir akan mendorong pembangunan-pembangunan sarana
perekonomian lainnya seperti akses jalan, pertokoan, fasilitas
rekreasi dan hiburan, dan usaha jasa yang dibutuhkan wisatawan
seperti jasa transportasi perjalanan, jasa pemandu wisata, dan
lain-lain. Banyaknya dampak peluang usaha dari pembangunan
pariwisata di daerah pesisir diharapkan dimanfaatkan
masyarakat sekitar sebagai peluang usaha selain pekerjaan
sektor perikanan. Peluang usaha yang bervariasi ini akan
meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam menghadapi
masalah kemiskinan. Makalah ini membahas dampak
industrialisasi pariwisata terhadap kemiskinan masyarakat
pesisir. Makalah ini dilatarbelakangi pertanyaan penulis,
yaitu bagaimana industrialisasi pariwisata menjadi solusi
dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.
5
METODOLOGI
Penulis mengkaji dampak industrialisasi pariwisata
terhadap kemiskinan masyarakat pesisir dengan paradigma kajian
ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang memiliki paradigma
fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma
perilaku sosial.3 Paradigma fakta sosial merupakan paradigma
yang memusatkan perhatian pada fenomena fakta sosial, struktur
sosial, dan institusi sosial serta pengaruhnya terhadap
pikiran dan tindakan individu. Paradigma definisi sosial
merupakan paradigma yang memusatkan perhatian pada cara
individu/kelompok mendefinisikan situasi sosial mereka dan
mempelajari pengaruh definisi sosial ini terhadap tindakan dan
integrasi berikutnya. Sedangkan paradigma perilaku sosial
merupakan paradigma yang memusatkan perhatian pada hadiah
(rewards) yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman
(punishments) yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan.
Penulis menggunakan satu dari tiga paradigma tersebut,
yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial
diawali dari teori Max Weber tentang tindakan sosial. Bagi
Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami
tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya dengan
menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut.4 Weber membedakan
empat tindakan sosial yaitu zweck rational, tindakan sosial
berdasarkan pertimbangan manusia yang rasional ketika
menanggapi lingkungan diluar dirinya dalam rangka usahanya
3 lihat Ritzer, G dan Goodman, D J. 2003. Hal A-13 – A-15.4 lihat Hotman M. Siahaan. 1986. Hal 200.
6
memenuhi kebutuhan hidup; wert rational, tindakan sosial yang
rasional yang berdasarkan nilai-nilai absolut seperti nilai
etis, estetis, keagamaan, atau nilai lain yang diyakini;
affectual, tindakan sosial yang timbul dari dorongan emosional;
traditional, tindakan sosial yang berorientasi pada hukum
normatif dari tradisi budaya masyarakat pada masa lampau.
Keempat tindakan sosial inilah yang menurut Weber akan
memperngaruhi pola-pola hubungan sosial serta struktur sosial
masyarakat.
Dengan paradigma definisi sosial, makalah ini membahas
bagaimana cara masyarakat pesisir mendefinisikan situasi
sosial yang dihadapi mereka dan pengaruh definisi sosial ini
terhadap tindakan dan integrasi berikutnya. Situasi sosial
yang dimaksud adalah situasi sosial yang diakibatkan adanya
industrialisasi pariwisata yang terdapat di daerah mereka.
Definisi sosial masyarakat terhadap situasi sosial tersebut
lalu mempengaruhi respon atau tindakan kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dengan paradigma
definisi sosial ini akan diketahui bagaimana hubungan antara
kedua varibel penelitian ini, yaitu hubungan antara
industrialisasi pariwisatan dan kemiskinan masyarakat pesisir.
Namun, kelemahan dari penelitian ini terletak pada metode
observasi yang hanya dilakukan sebatas observasi pada
literatur atau kajian pustaka. Faktor keterbatasan waktu dan
biaya menyebabkan penulis tidak melakukan observasi langsung
pada masyarakat pesisir disekitar obyek pariwisata. Meskipun
dengan data-data sekunder, penulis tetap mampu menemukan
benang merah permasalahan dalam hubungan antara variabel
7
penelitian. Dan dengan menggunakan teori-teori yang relevan,
penulis menganalisis permasalahan hingga menemukan jawaban
atas masalah dalam pembahasan makalah ini.
8
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesungguhnya, pariwisata telah dimulai sejak dimulainya
peradaban manusia itu sendiri, ditandai oleh adanya pergerakan
manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya.
Dalam melakukan kegiatan wisata, wisatawan dipengaruhi oleh
faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong
merupakan faktor internal yang bersifat psikologis, sedangkan
faktor penarik merupakan faktor yang berasal dari obyek wisata
yang berupa tawaran atau promosi. Faktor pendorong yang
bersifat psikologis antara lain kebutuhan hiburan atau
relaksasi dari kejenuhan rutinitas kerja, menjalin hubungan
kekerabatan dan keakraban dalam keluarga atau pertemanan,
menunjukkan gengsi atas kelas sosial dan gaya hidup
berdasarkan tujuan wisata, alasan pembelajaran atau
pengetahuan yang ingin didapatkan ketika berwisata, dan
dorongan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan, faktor penarik yang
ditawarkan oleh obyek wisata antara lain keindahan alam,
wahana hiburan, fasilitas penunjang disekitar obyek wisata,
akses menuju obyek wisata, biaya yang harus dikeluarkan,
tingkat keamanan, dan karateristik kebudayaan. Faktor-faktor
penarik inilah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan
industri pariwisata. Prinsip industri pariwisata untuk
menghadirkan ‘surga’ dan memanjakan wisatawan adalah modal
utama menjadi obyek wisata unggulan. Seperti industri wisata
di Bali dengan konsep Pulau Dewata (God’s Island) yang memanjakan
para wisatawan telah terbukti menjadi obyek wisata primadona
oleh wisatawan domestik dan mancanegara.
9
Industri pariwisata di daerah lain seperti Ancol Theme
Park yang berdiri tahun 1966. Ancol merupakan industri
pariwisata di Jakarta yang berlokasi dekat pantai (rekreasi
dan resor) dan kegiatan usaha penunjang: entertainment, konvensi
dan wisata belanja Area pariwisata terintegrasi seluas 552 Ha.
Di Jawa Tengah terdapat obyek pariwisata Karimunjawa yang pada
awalnya merupakan salah satu kawasan Cagar Alam Laut di
Jepara. Dengan berkembangnya waktu Kepulauan Karimunjawa
diputuskan menjadi Taman Nasional Karimunjawa dan sekarang ini
menjadi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun manca negara
untuk berwisata. Pulau Karimunjawa adalah desa nelayan dengan
penduduk yang ramah, deretan pegunungan dengan jalur tracking
menantang, pantai dengan kekayaan laut yang masih alami dan
indah, serta pemandangan matahari terbenam yang mempesona. Di
Jawa Timur terdapat Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang terletak
di pesisir utara pantai Jawa, tepatnya di kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan. WBL berdiri sejak tahun 2004 sebagai hasil
pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Kodok yang telah ada
sebelumnya. WBL menawarkan oase tersendiri bagi wisatawan
dengan memadukan konsep wisata bahari dan dunia wisata dalam
areal seluas 11 Ha. Di Kepulauan Raja Ampat, Papua, terdapat
kawasan pariwisata dengan produk unggulan wisata penyelaman.
Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan salah satu dari
sepuluh perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia dan
juga diakui sebagai nomor satu untuk kelengkapan flora dan
fauna bawah air. Kepulauan lain dengan potensi perairan
sebagai diving site ada di Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara.
Taman laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 Ha dengan lima
10
pulau yang berada di sekitarnya. Taman laut Bunaken memiliki
20 titik penyelaman (dive spot) dengan kedalaman bervariasi
hingga 1.344 meter dan terdapat underwater great walls, yang
disebut juga hanging walls, atau dinding-dinding karang raksasa
yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Di Pulau
Kalimantan Timur juga terdapat Taman Laut, tepatnya di
Kepulauan Derawan Kabupaten Berau. Dengan potensi pasir putih
pantainya yang alami, pemandangan sunrise dan sunset, dan juga
kekayaan flora dan fauna bawah air. Di Pulau Sumatera terdapat
obyek pariwisata Danau Toba yang merupakan sebuah danau
vulkanik terbentuk akibat ledakan gunung berapi pada 69.000 -
77.000 tahun lalu. Setelah ledakan tersebut, terciptalah
kaledra (cekungan pada tanah sesudah letusan vulkanik) yang
kemudian terisi oleh air dan kita ketahui sebagai Danau Toba
sekarang. Danau terluas di dunia ini memiliki luas 3.000 Km2
juga terdapat pulau kecil di tengah danau yang bernama Pulau
Samosir.
Industrialisasi Pariwisata
Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di
dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa
di berbagai negara. Diawal terbentuknya negara Indonesia,
pemerintah langsung membentuk Honet (Hotel National and Tourism)
tahun 1946, sebuah lembaga negara yang diberi tugas
mengembangkan pariwisata Indonesia. Lalu tahun 1955 berdiri
Natour dan YTI (Yayasan Tourisme Indonesia). Istilah
‘pariwisata’ dicetuskan pada Kongres II YTI tanggal 12-14 Juni
1958 di Tretes, Jawa Timur. Istilah ‘pariwisata’ diartikan11
sebagai international tourism, sedangkan untuk domestic tourism
dipopulerkan istilah ‘dharma wisata’. Dengan besarnya potensi
pariwisata yang dimiliki bangsa Indonesia dalam keindahan alam
dan keunikan sosial budaya, pemerintah sangat menaruh harapan
pada industri pariwisata sebagai ‘komoditas ekspor’ sebagai
penghasil devisa terbesar dan mampu menggantikan peranan
industri sektor migas. Mayoritas wilayah Indonesia yang
memiliki potensi pariwisata terdapat di wilayah pesisir
pantai. Sebagai negara yang memiliki daerah garis pantai
terpanjang kedua didunia, harusnya pemerintah mampu
memanfaatkan potensi ini menjadi industri pariwisata dalam
rangka pembangunan nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI (Menparekraf RI) Mari Elka Pangestu menyatakan
bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 2006 hingga 2010
menunjukkan peningkatan indeks prestasi pada peringkat keempat
penerimaan devisa negara. Pernyataan dipaparkan pada rilis
kementrian pada indeks 2006-2010 pada rilis resmi kementerian
pariwisata awal Agustus 2012. Laporan Kementerian menunjukkan,
pada tahun 2006 Kemenparekraf RI menempati peringkat keenam
penerimaan devisa sebesar 4.447,97 Dolar AS. Pada tahun 2007
total penerimaan devisa sebesar 5.345,98 Dolar AS, selanjutnya
tahun 2008 sebesar 7.377,00 Dolar AS, tahun 2009 sebesar
6.298,02 Dolar AS, dan ditutup pada akhir tahun 2010 menduduki
ranking keempat dengan total penerimaan devisa sebesar 7.603,45
Dolar AS.
Dari perspektif sosiologi, industri pariwisata terdapat
tiga dimensi interaksi yaitu dalam kultural, politik, dan
ekonomi. Dalam dimensi interaksi kultural terjadi akulturasi
12
budaya. Budaya yang dimiliki masyarakat lokal bertemu dengan
budaya yang dibawa para wisatawan. Dimensi interaksi politik
dalam industri pariwisata terdapat dua jenis hubungan
kerjasama antar daerah, antar etnis atau antar bangsa. Yang
pertama adalah hubungan kerjasama antar daerah, antar etnis,
atau antar bangsa dalam pengembangan industri pariwisata.
Seperti hubungan kerjasama pariwisata antar negara ASEAN dan
hubungan kerjasama pariwisata Indonesia dengan Australia. Yang
kedua adalah hubungan kerjasama yang mengakibatkan
ketergantungan salah satu pihak, melakukan eksploitasi potensi
pariwisata hingga bentuk neokolonialisme yang sebenarnya
merugikan salah satu pihak. Misalnya ketergantungan
peenerimaan devisa pariwisata dari wisatawan luar negeri,
ketergantungan terhadap wahana atau fasilitas yang diproduksi
dari luar negeri dan ketergantungan terhadap modal investasi
asing dalam pembangunan industri pasriwisata. Sedangkan
dimensi interaksi ekonomi terjadi dalam transaksi jual-beli
dan terbukanya berbagai kesempatan usaha ekonomi yang
mendukung kegiatan pariwisata.
Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang secara
langsung bersentuhan dan melibatkan masyarakat setempat. Pada
mulanya, industri pariwisata terbentuk dari sebuah daerah atau
kawasan yang memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan.
Dalam pengembangan atau pembangunan kawasan potensi wisata
menjadi industri pariwisata, terjadi interaksi langsung antara
pemerintah, pengembang (developer), dan masyarakat setempat.
Sebuah kawasan potensi wisata yang meskipun terdapat di tempat
terpencil atau jauh dari pusat keramaian, ketika dikembangkan
13
menjadi industri pariwisata maka akan sangat mempengaruhi
masyarakat setempat dalam berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang masih tradisional
mendadak harus ikut beradaptasi dengan pembangunan industri
pariwisata di daerah mereka. Dalam strategi pembangunan
industri pariwisata Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana
untuk membangun, memperbaiki, dan mengembangkan infrastruktur
pendukung di kawasan pariwisata, membenahi perundang-undangan
yang berkaitan dengan paspor dan visa, membenahi peraturan-
peraturan tentang usaha ekonomi sektor kepariwisataan seperti
perhotelan, restoran, biro perjalanan, dan pramuwisata, serta
perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan,
kelestarian flora fauna, dan peninggalan sejarah budaya.
Sebagai sebuah kegiatan ekonomi, industri pariwisata lebih
dipandang untuk mengejar produktivitas untuk menghasilkan laba
bagi pengusaha atau pengembang industri pariwisata. Konsep
pembangunan industri pariwisata yang hanya berorientasi pada
produktivitas ekonomi tanpa menjaga aspek sosial masyarakat
akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi. Manusia (tenaga
kerja) dipandang sebagai faktor produksi sama halnya dengan
faktor produksi tanah, alam dan manajemen. Karena hanya
dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mekanis,
maka tenaga kerja manusia distandarisasikan berdasarkan
indikator keberhasilan. Pembangunan dengan sifat etnosentrisme
yang memaksakan penerapan teori-teori pembangunan modernisasi
dan sentralisasi pengambilan keputusan, menjadikan masyarakat
lokal tidak mempunyai peran dalam kegiatan pembangunan yang
mempengaruhi hidup dan masa depan mereka. Hingga konsep ini
14
mendapat kritik tajam dari faham humanisme tentang pembangunan
harus diusahakan untuk ‘memanusiakan manusia’. Dikalangan ahli
pembangunan muncul wacana bahwa pembangunan sesungguhnya
adalah untuk manusia, sebagai suatu proses belajar (social
learning process), dan dalam hal ini manusia merupakan pusat dan
penggerak sekaligus untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan
sesuai konsep people centred development. Sehingga, manusia bukan
sekedar faktor produksi.
Dampak industri pariwisata merupakan wilayah kajian yang
paling banyak mendapat perhatian dalam literatur, terutama
dampak terhadap masyarakat lokal. Dampak pariwisatan terhadap
kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal: dampak terhadap
pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja dan
peluang usaha, dampak terhadap pendapatan pemerintah dari
devisa dan pajak, dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Tetapi masalah pariwisata bukan hanya masalah ekonomi,
melainkan juga masalah sosial, budaya, politik dan sebagainya.
Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks dengan
berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi
antar sesama. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata
telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat dan sudah
hampir menyentuh semua masyarakat dunia, hingga kepada
masyarakat terpencil kini sudah dirambah pariwisata dengan
berbagai derajat pengaruh. Pariwisata telah terbukti menjadi
salah satu primemover dalam perubahan sosial budaya.
Masyarakat Pesisir
15
Mayoritas mata pencaharian masyarakat pesisir adalah
nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan dipercayai memiliki nilai-
nilai luhur yang tinggi. Nelayan adalah pekerjaan yang
bergantung pada kondisi alam dan sumber daya ikan yang ada,
artinya nelayan mempercayai kehidupannya bergantung pada
berkah yang diberikan oleh Tuhan. Budaya ritual petik laut
atau sedekah laut atau larung saji yang dilakukan nelayan
merupakan bentuk ucapan syukur dan doa kepada Tuhan agar
memberkahi dengan kelimpahan kakayaan laut dan keselamatan
nelayan ketika menangkap ikan.
Selain nelayan, masyarakat pesisir bekerja di sektor
nonperikanan seperti pemasaran ikan laut, usaha produksi
garam, produksi pengolahan rumput laut, kerajinan tangan dari
benda-benda laut, dan pekerjaan di sektor-sektor lain. Variasi
pekerjaan masyarakat pesisir ini perlu dikembangkan agar tidak
tergantung sepenuhnya terhadap pekerjaan nelayan. Dalam
kehidupan masyarakat pesisir terdapat faktor-faktor sosial-
budaya yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat pesisir
menghadapi kemiskinan. Faktor kondisi alam pada musim kemarau
mengakibatkan masa paceklik sehingga nelayan kesulitan
memperoleh ikan, faktor keterampilan nelayan dan faktor
teknologi alat penangkapan ikan yang berpengaruh terhadap
jumlah hasil tangkapan ikan, persaingan antara nelayan
tradisional dan nelayan moderen yang sering menimbulkan
konflik sosial, hubungan kerja antara pemilik perahu dan
nelayan buruh yang dianggap kurang menguntungkan nelayan
buruh, adanya persepsi budaya masyarakat pesisir yang boros
ketika musim ikan, dan ketergantungan terhadap pekerjaan
16
nelayan serta terbatasnya peluang kerja di sektor
nonperikanan. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir
dalam menghadapi kemiskinan, pemerintah melalui Kementrian
Kelautan dan Perikanan memprogramkan pemberdayaan masyarakat
pesisir. Tujuan program-program pemberdayaan masyarakat
tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pesisir melalui pengembangan kesejahteraan ekonomi,
peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia, dan
penguatan kelembagaan sosial ekonomi. Memberdayakan masyarakat
pesisir agar mampu diikutsertakan dalam pengelolahan kekayaan
perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
Masyarakat pesisir berbeda dari masyarakat lain seperti
masyarakat petani atau masyarakat perkotaan. Masyarakat
pesisir, terutama nelayan, memiliki ketergantungan terhadap
sumber daya alam berupa perikanan dan kelautan. Mereka
mempunyai strategi bertahan hidup yang melahirkan pola-pola
kebudayaan dan menjadi karateristik yang berbeda dari pola
kebudayaan masyarakat lain. Dari pola kebudayaan itu terbentuk
struktur sosial dan pranata sosial budaya. Dua pranata
strategis yang dianggap penting untuk memahami kehidupan
sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah pranata penangkapan
dan pranata pemasaran ikan.5 Kedua pranata ini menjadi sumber
potensial timbulnya kemiskinan struktural pada masyarakat
nelayan. Kedua pranata sosial ekonomi tersebut membentuk
persepsi ketidakberdayaan terhadap sistem stratifikasi
pekerjaan nelayan antara pemilik perahu, pengepul atau
pedagang ikan, dan nelayan buruh. Struktur sosial budaya yang
5 lihat Kusnadi. 2003. Hal 4.17
tercemin dalam kedua pranata tersebut memiliki kontribusi
besar dalam membentuk corak pelapisan sosial ekonomi
masyarakat pesisir. Mereka yang menempati lapisan sosial
ekonomi atas adalah para pemilik perahu dan pengepul ikan yang
sukses, pada lapisan sosial ekonomi tengah ditempati juragan
atau pemimpin nelayan, sedangkan nelayan buruh terdapat pada
lapisan sosial ekonomi bawah. Dalam struktur sosial dan
pranata sosial demikian, masyarakat pesisir sulit terjadi
mobilitas sosial vertikal.
Untuk mengatasi kemiskinan struktural akibat struktur
sosial dan pranata sosial inilah dibutuhkan peran perempuan.
Dukungan istri nelayan dalam membantu tanggung jawab sosial
ekonomi keluarga terdapat dalam diversifikasi pekerjaan di
darat. Dengan diversifikasi pekerjaan di darat, nelayan tidak
lagi bergantung sepenuhnya dari sumber daya alam perikanan dan
kelautan. Dari sisi tanggung jawab sosial ekonomi keluarga
pada masyarakat nelayan, suami dan istri nelayan berposisi
sejajar dan saling melengkapi. Kaum perempuan dan pranata-
pranata sosial budaya yang ada merupakan potensi pembangunan
masyarakat pesisir yang bisa diberdayakan untuk mengatasi
kemiskinan. Dalam ketergantungan terhadap kegiatan penangkapan
ikan perlu disediakan kesempatan usaha/pekerjaan lain diluar
sektor perikanan agar meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi tekanan-tekanan ekonomi.
Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial - Ekonomi
18
Pembahasan mengenai kemiskinan sering dikatakan sebagai
akibat dari kesenjangan/ketimpangan. Seperti pengertian yang
menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah
klasik yang sering muncul akibat adanya ketimpangan yang cukup
tajam pada aspek distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi
keluarga.6 Kemiskinan akibat kesenjangan ini disebut kemiskinan
struktural. Pembahasan lain membedakan antara kemiskinan dan
kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan
(deprevation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar
yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi dimana didalamnya
terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi (economic
resources).7 Pada pembahasan kedua ini terdapat pemisahan arti
dari kemiskinan dengan kesenjangan. Maksudnya, kemiskinan
terjadi pada masyarakat, dimana secara umum kehidupan
masyarakat tersebut mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi
kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan
kesehatan. Lalu ketika terjadi persaingan dalam upaya
pemenuhan kebutuhan hidup atau ketika dibandingkan dengan
tingkat kesejahteraan masyarakat lain, maka terbentuklah
sebuah kelas pemisah yang disebut kesenjangan. Dalam
kesenjangan itu kelompok yang kuat mempunyai akses lebih kuat
pada sumber-sumber ekonomi daripada kelompok lain yang
tergolong lemah. Hingga struktur sosial juga menekan kelompok
lemah dan menyebabkan mereka tetap berada dalam posisi
kemiskinan, bahkan kemiskinan yang turun temurun. Kemiskinan
ini disebut kemiskinan struktural.
6 lihat Soetrisno R. 2001. Hal 2.7 lihat Sunyoto Usman. 1998. Hal 33.
19
Dalam masyarakat, dapat ditemukan dua macam keadaan: (1)
terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan, atau (2) tidak
terdapat kemiskinan tetapi boleh jadi masih ada kesenjangan.8
Dalam masyarakat pesisir yang terdapat pembangunan industri
pariwisata menimbulkan kemiskinan sekaligus kesenjangan. Di
sekitar daerah wisata di tepi pantai dibangun resort, vila dan
akomodasi pariwisata lainnya. Namun, masyarakat pesisir selama
ini cenderung hanya menjadi objek. Buktinya, di tengah
pembangunan pariwisata yang pesat, mereka masih terhimpit
dalam kemiskinan. Masyarakat pesisir belum maksimal merasakan
dampak ekonomis kehadiran pariwisata. Seperti industri
pariwisata di Bali, kawasan pesisir dengan lautnya juga
dimanfaatkan untuk aktivitas agama dan adat. Sementara bagi
kalangan pengembang (developer) dan pengusaha, pantai merupakan
tempat yang strategis untuk membangun hotel dengan potensi
suasana dan pemandangan yang indah. Yang menjadi permasalahan
adalah ketika kepentingan masyarakat pesisir kerap diabaikan.
Kegiatan pariwisata di wilayah pesisir lebih menyentuh para
pemilik modal besar saja, sedangkan masyarakat pesisir hanya
menjadi penonton. Banyak program pemberdayaan masyarakat namun
dalam praktiknya justru kebanyakan masyarakat diperdayai hanya
untuk kepentingan pihak tertentu. Bentuk kekuasaan yang
dimiliki pihak pengusaha bisa berdampak negatif pada usaha-
usaha ekonomi kecil yang ada disekitar industri pariwisata.
Seperti pedagang kecil disekitar Ancol Theme Park, Jakarta,
yang protes terhadap peraturan-peraturan yang harus dijalankan
oleh para pedagang misalnya saja pada saat hari raya besar
Capgomeh yang umumnya dirayakan pada malam hari. Saat hari8 Ibid
20
raya besar ini dinantikan oleh para pedagang sebagai
kesempatan memperoleh penghasilan yang besar, tetapi pihak
Ancol menetapkan untuk melaksanakan penutupan pintu gerbang
masuk utama menuju lokasi objek wisata yang akhirnya
mematahkan harapan para pedagang yang akan memperoleh
penghasilan lebih.
Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat (PPBM)
Faktor sosial budaya tersebut yang perlu diperhatikan
dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir.
Kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat pesisir harus beradaptasi pada perilaku sosial
budaya masyarakat setempat serta mendorong masyarakat untuk
aktif sebagai subyek atau pelaku utama secara mandiri mampu
mengatasi persoalan kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi.
Banyak desa-desa yang berada di wilayah pesisir dan wilayah
dataran tinggi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi
desa wisata. Pengembangan desa wisata mampu mendukung upaya
penanggulanan kemiskinan di pedesaan dengan jalan
memberdayakan masyarakat lokal dalam membangunan
kepariwisataan di desanya. Salah satu upaya mengembangkan desa
wisata dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata yang mulai
dilaksanakan sejak tahun 2007.
Pengertian Desa Wisata Desa Wisata (Muliawan, 2008) adalah
desa: (1) yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata
yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan
21
maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan; (2) yang
dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan
pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata
lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan
terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan
kunjungan wisatawan ke desa tersebut; (3) serta mampu
menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat
meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
setempat. Kriteria Desa Wisata: (1) memiliki potensi keunikan
dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik
berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun
kehidupan sosial budaya kemasyarakatan; (2) memiliki dukungan
dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan
kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa :
akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan
wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya; (3) memiliki
interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari
kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut; (4) adanya
dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat
terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan
kepariwisataan (sebagai desa wisata).
Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat (PPBM) kini
merupakan kecenderungan baru yang banyak dibicarakan orang.
Dalam PPBM ini peran masyarakat menjadi kunci utama, di mana
masyarakat lokal diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam
melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya.
Selain itu, masyarakat sendiri juga menentukan berbagai
kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta membuat keputusan demi
22
kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini pengelolaan pesisir
berbasis masyarakat mestinya menyertakan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang
memegang peranan utama adalah masyarakat pesisir itu sendiri,
sedangkan pendampingnya hanya mendampingi, memotivasi dan
mengarahkan serta memfasilitasi.
Contoh industri pariwisata di Bali. Pemberdayaan
masyarakat pesisir memiliki hubungan dimensi interaksi yang
erat dan penting dengan industri pariwisata setempat. Dapat
diasumsikan pemberdayaan masyarakat pesisir di suatu wilayah
berhasil dilakukan dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung
di wilayah pesisir tersebut serta akan lebih terjamin
kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Hal ini dapat terjadi
karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di
wilayah pesisir merupakan salah satu bagian, baik langsung
maupun tak langsung, terkait dengan kegiatan pariwisata yang
dilakukan di wilayah pesisir. Sebagai salah satu contoh
kegiatan yaitu memotivasi masyarakat pesisir untuk
membudidayakan terumbu karang, di mana pihak pendamping
pemberdayaan masyarakat ini bertugas memberikan teknologinya
dan memberikan percontohan uji cobanya dengan melibatkan
langsung masyarakat pesisir. Melalui pembudidayaan terumbu
karang maka kelak kalau berhasil akan dapat menambah
diversifikasi mata pencaharian masyarakat tersebut. Kegiatan
budi daya terumbu karang ini sebagai sarana rehabilitasi
lingkungan dan mengurangi abrasi pantai, juga memberi dampak
yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
23
Keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat
ditentukan tingkat kesungguhan masyarakat pesisir dalam
memanfaatkan dan mengembangkan dana program pemberdayaan
secara bertanggung jawab dan kerjasama antar instansi terkait
sebagai pelaksana atau sebagai pengawas program pemberdayaan,
serta metode pendekatan kemasyarakatan dalam melaksanakan
program pemberdayaan. Pendekatan kemasyarakatan yang tepat
akan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat
pesisir.
24
KESIMPULAN
Dari pembahasan tentang industrialisasi pariwisata,
masyarakat pesisir, dan kemiskinan masyarakat pesisir, penulis
menyimpulkan bahwa industrialisasi pariwisata memiliki dampak
terhadap kemiskinan masyarakat pesisir. Dampak tersebut
ditentukan oleh bagaimana cara masyarakat pesisir
mendefinisikan situasi sosial yang dihadapi. Situasi sosial
yang dimaksud adalah situasi sosial yang diakibatkan adanya
industrialisasi pariwisata yang terdapat di daerah mereka.
Definisi sosial masyarakat terhadap situasi sosial tersebut
lalu mempengaruhi respon atau tindakan kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat setempat
Dalam pola kebudayaan lokal, pranata sosial dan struktur
sosial ternyata menjerat masyarakat pesisir dalam kemiskinan.
Pemberdayaan masyarakat pesisir harus memberikan kesempatan
diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Pembangunan
industri pariwisata di kawasan pesisir merupakan satu bentuk
kesempatan terhadap masyarakat setempat untuk mengelolah
sebuah usaha perekonomian yang bisa meningkatkan kemampuan
mereka dalam menghadapi kemiskinan. Keberhasilan program-
program pemberdayaan masyarakat ditentukan tingkat kesungguhan
masyarakat pesisir dalam memanfaatkan dan mengembangkan dana
program pemberdayaan secara bertanggung jawab dan kerjasama
antar instansi terkait sebagai pelaksana atau sebagai pengawas
program pemberdayaan, serta metode pendekatan kemasyarakatan
dalam melaksanakan program pemberdayaan. Pendekatan
25
DAFTAR PUSTAKA
Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid I.
Jakarta. Gramedia.
Kusnadi, M.A, Drs. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta.
LKiS.
Kusnadi, M.A, Drs. 2006. Perempuan Pesisir. Yogyakarta. LkiS.
Pendit, Nyoman S. 1994. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana.
Jakarta. Anem Kosong Anem
Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata.
Yogyakarta. ANDI.
Ritzer, G dan Goodman, Douglas J. 2003. Teori Sosiologi Modern.
Jakarta. Kencana.
Siahaan, Hotman M. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi.
Jakarta. Erlangga.
Soetrisno R. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan
Kemiskinan. Yogyakarta. Philoshophy Press.
Sunyoto Usman, Dr. 1998. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Tulungen, J Johnnes, dkk. 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. USAID – Indonesia Coastal
Resources Management Project.
http://www.kp3k.kkp.go.id/pnpmkp/tentang.php
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia
27