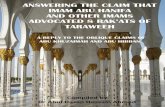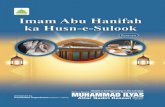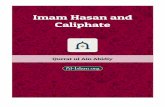Talal Abu-Ghazaleh Founder and Chair, Talal Abu-Ghazaleh ...
BAB III AUTOBIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of BAB III AUTOBIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ...
41
BAB III
AUTOBIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I
A. Imam Abu Hanifah
1. Biografi Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah bersamaan
(659 Masehi). Sebagaian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan
pada tahun 61 Hiriyah, pendapat ini sangat tidak berdasar, karena yang
sebenarnya ialah pada tahun 80 Hijiryah (659 Masehi) menurut pendapat
yang pertama.1 Nama asli Imam Hanafi adalah Abu Hanafi An-Nu‟man
dan keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli – Taimullah dan
akhirnya Tsa‟labah, ahli sejarah adapula yang berpendapat bahwa Imam
Hanafi berasal dari bangsa Arab suku Bani Yahya bin As‟ad dan da pula
yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rasyd al-Anshari.
Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan dari bangsa Arab asli,
tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bansa Arab), dan beliau dilahirkan
ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan,
pemerintahan Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul malik bin Marwan
(Raja dari Bani Umayyah yang kelima). Menurut riwayat: bahwa ayah
beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah diajak datang berziarah oleh
ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a, maka dikala itu di
do‟akan oleh beliau (Sahabat Ali) : Mudah-mudahan dari antara
keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang yang baik-baik
serta luhur.
Imam Abu Hanifah sesudah berputra beberapa orang putra, yang di
antaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka dari karenanya beliau
mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Ini,
menurut satu riwayat, dan menurut riwayat yang lain. Sebabnya beliau
mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin
1 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, (Jakarta,
Bumi Aksara. 1993), hlm. 14
42
melakukan ibadah kepada Allah SWT dan sungguh-sungguh mengerjakan
kewajiban dalam agama. Selanjutnya, setalah ijtihad dan buah
penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti
oleh orang banyak, maka ijtihad beliau itu dikenal orang dengan sebutan
“Madzhab Imam Hanafi.”2
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah
Suatu hari, ketika Imam Abu Hanifah tengah melintasi rumah
Imam Sya‟bi, seorang ulama terpelajar dari Kufah, Sya‟bi keliru
menganggapnya sebagai pelajar dan bertanya : “Hendak kemana engkau,
hai anak muda ?” Imam Abu Hanifah lalu menyebutkan seorang saudagar
yang hendak ditemuinya. Maksud pertanyaanku, lanjut Sya‟bi, “Siapa
namamu ?” Jawab Imam Abu Hanifah, “tidak seorang pun”. Kemudian
Sya‟bi berkata : “Aku melihat tanda-tanda kecerdasan yang ada pada
dirimu, maka seyogyanya engkau duduk bersama-sama orang yang
terpelajar”. Pertanyaan Sya‟bi itu seakan-akan memercikan cahaya baru di
hati sanubari Imam Abu Hanifah, setelah itu dia pun mulai giat belajar
sehingga menjadi salah satu seorang Imam besar di lapangan fiqih dan
hadits.3
Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira’az,
hadits, nahwu, sastra, syi‟ir, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada
masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia
menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena
ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan
Khawarij yang di doktrin ajarannya sangat ekstrim.
Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah
yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang
cenderung rasional, di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh
2 Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, (Jakarta, Bulan
Bintang, 1990), hlm. 19 3A. Rahman, I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah),
(Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 121
43
Abdullah bin Mas‟ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah
Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha‟i, lalu Hammad ibn Abi
Sulaiman al-Asy‟ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah
seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari „Alqamah ibn
Qais al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pikir fiqh yang
terkenal di Kufah dari golongan Tabi‟in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman
itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.4
Setalah itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk
mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di
Kufah. Sepeninggal Hammad, Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat
Imam Hanafi menjadi kepala Madrasah. Selama ini ia mengabdi dan
banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu
merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi yang dikenal
sekarang ini. Imam Abu Hanifah berhasil mendidik dan menimpa ratusan
murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari
muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti
Abbasiyah, Saljuk, „Utsmani dan Mughal.5
3. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah
a) Guru-Guru Imam Abu Hanifah
Adapun guru-guru beliau pada waktu itu kebanyakannya ialah
para ulama Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in diantaranya ialah:
a) Abdullah bin Mas‟ud (Kufah)
b) „Ali Abi Thalib (Kufah)
c) Ibrahim Al-Nakhai (wafat 95 H)
d) Amir bin Syarahil Al-Sya‟bi (wafat 104 H)
e) Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau
adalah orang alim ahli fiqh yang paling mashur pada masa itu
4 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 96 5 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 97
44
Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18
tahun lamanya.
f) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
g) Imam Nafi‟ Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
h) Imam Salamah bin Kuhail
i) Imam Qatadah
j) Imam Rabi‟ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-
ulama besar lainnya6.
b) Murid-Murid Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-
karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya,
maka banyak murid-murid yang belajar kepadanya hingga mereka
dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid
Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar
dengannya di antaranya ialah:
a) Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibarahim Al-Anshary, dilahirkan
pada tahun 113 H. beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-
macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan
keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan
hadist dari Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Hasyim bin Urwah
Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf
termasuk golongan ulama ahli hadist yang terkemuka. Beliau wafat
pada tahun 183 H.
b) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan
dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil bertempat tinggal
dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana.
Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara
Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di
kota Ryi.
6 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki,
Syafi’iy, Hambali, (Jakarta: Bulan Bintang,1955), cet ke-2, hlm. 23.
45
c) Imam Zafar bin Hudzail bin Qias Al-Kufy, dilahirkan pada tahun
110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu
hadist, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu
akal atau ra’yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang
yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan
menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanafi yang dikenal dengan
qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari yang lainnya pada tahun 158
H.
d) Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam
Abu Hanifah yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau
wafat pada tahun 204 H19.
Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah
yang terakhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah
ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai
kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal
hukum yang bertalian dengan agama.
4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra’yi. Dalam
menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur‟an
ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan
ra’yi dan khabar had. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau
menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.7
Meskipun demikian, telah diriwayatkan dari Imam Hanafi
pendapat-pendapat yang menunjukkan garis besar metode istinbathnya dan
dalil-dalil yang digunakannya. Di antaranya ia berkata, “Aku berpegang
pada kitab Allah jika aku dapati hukum padanya. Jika tidak maka aku
berpegang pada Sunnah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatinya dalam
kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, aku berpegang pada ucapan sahabat,
7 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 98
46
aku berpegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki dan aku
tinggalkan siapa yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan
mereka kepada ucapan selian mereka. Namun ketika sampai pada masa
Ibrahim, asy-Sya‟bi, Ibnu Sirrin, „Atha‟, dan Sa‟id bin Musayyib (para
mujtahid dari tabi‟in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”8
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan
mazhab Hanafi adalah:
a. Al-Qur‟an
Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pesan al-Qur‟an
tidak semuanya qath’i dalalah9. Ada beberapa hal yang memerlukan
interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur‟an, terutama
terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah umum antar
manusia10
, dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah
tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum terhadap suatu
masalah lebih besar. Hal itu karena di buktikan baik oleh Imam Abu
Hanifah sendiri maupun murid-muridnya dan karena itu juga sebagai
mahzab yang Umari, mazhab liberalis dan rasionalis11
.
Dalam memahami al-Qur‟an, ulama Hanafiyah tidak hanya
melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi
mereka juga melakukan penelaahan terhadap ‘am dan khas ayat al-
Qur‟an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-
8 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’at, (Jakarta: Robbani Press, 2008),
cet. ke-1, hlm. 201 9Menurut Abu al-Ainain Badran al-Ainain seorang guru besar ushul al Fiqh di
Mesir bahwa qath’i adalah sesuatu yang menunjuk kepada hukum tertentu dan tidak
mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan zanni adalah dalil (ayat atau hadis)
yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Baca lanjut : Aziz
Dahlan, Ensinklopedi Hukum Islam, julid 5, Cet. V, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Houve,
2001), hlm, 1454 10
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 159. 11
Jalaludin Rahmat, Dari Mazhab Skripturalisme Ke Mazhab Liberal Dalam
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 159
47
ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama
Hijaz yang semazhab dengan mereka12
.
b. Al-Sunnah
Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah al-
Sunnah. Martabat al-Sunnah yang terletak di bawah al-Qur‟an. Imam
Abu Yusuf berkata, “Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih
alim tentang menafsirkan hadits dari pada Imam Abu Hanifah. Ia
adalah seorang yang mengerti tentang penyakitpenyakit hadits dan
menta’dil dan mentarjih hadits13
. Tentang dasar yang kedua ini,
Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan al-Sunnah yang mutawatir14
,
masyhur15
, dan shahih16
. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan begitu
juga ulama Hanafiyah agak selektif dalam menetapkan syarat-syarat
yang dipergunakan untuk menerima hadits ahad17
.
Imam Abu Hanifah menolak hadits ahad18
apabila berlawanan
dengan al-Qur‟an baik makna yang diambil dari nash atau yang
12
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 160. 13
Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki,
Syafi’iy, Hambali, (Jakarta: Bulan Bintang,1955), cet ke-2, hlm. 57 14
Hadits mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi
yang menurut adat, mustahil mereka bersepakat lebih dahulu untu berdusta. Baca lanjut :
Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 2 15
Hadits Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih
serta belum mencapai derajat mutawatir. Baca lanjut : Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits,
(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 2 16
Para ulama hadits memberikan definisi hadits shahih sebagai “hadits yang
sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama,
sampai berakhir pada Rasulullah Saw. atau kepada sahabat atau kepada tabiin, bukan
hadits yang syadz (controversial) dan terkena illat, yang menyebabkan cacat dalam
penerimannya. Baca lanjut : Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1997), 132 17
Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki,
Syafi’iy, Hambali, (Jakarta: Bulan Bintang,1955), cet ke-2, hlm. 57 18
Hadits ahad ialah hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih,
yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadits masyhur dan hadits mutawatir. Baca
lanjut : Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.
107
48
diambil dari illat hukum. Ali Hasan Abdul al-Qadir mengatakan,
“Musuh-musuh Imam Abu Hanifah (yang tidak senang dengan Imam
Abu Hanifah) menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar
terhadap hadits, ia memprioritaskan ra’yu (logika)”. Abu Salih al-Fura
menuturkan, “Aku mendengar Ibn Asbath berkata, “Imam Abu
Hanifah menolak 400 hadits19
.
Terhadap hadits mutawatir Imam Abu Hanifah menerimanya
tanpa syarat karena tingkat kehujjahannya qath’i, meskipun terdapat
pertentangan antara hadits mutawatir dengan akal, beliau
mendahulukan hadits mutawatir. Hal ini berbeda dengan hadits ahad,
beliau menerima dan mengamalkan hadits ahad apabila hadits tersebut
memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
Orang yang meriwayatkan tidak boleh berfatwa yang bertentangan
dengan hadits yang diriwayatkannya.
Hadits ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum yang sering
terjadi, sebab kalau menyangkut persoalan yang sering terjadi
mestinya hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi.20
Hadits ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum atau
dasardasar kulliyah21
.
c. Qaul al-Shahabah
Imam Abu Hanifah sangat mengahargai para sahabat. Dia
menerima, mengambil serta mengharuskan umat Islam
mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa Qaul al-
Shahabah maka ia mengambil salah satunya, jika tidak ada qaul al-
Shahabah pada suatu masalah tersebut maka ia berijtihad dan tidak
mengikuti pendapat tabi‟in. Menurut Imam Abu Hanifah Ijma‟
19
Jalaludin Rahmat, Dari Mazhab Skripturalisme Ke Mazhab Liberal Dalam
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 295 20Perawi adalah tiap-tiap yang menjadi perantara penyampaian matan. Baca
lanjut : A. Qadir Hasan, Ilmu Hadits, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 43 21
A. Qadir Hasan, Ilmu Hadits, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 43.
49
sahabat ialah kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu
masa sesudah Nabi SAW atas suatu urusan22
.
Ta’rif itulah yang disepakati ulama ahl-al-Ushul. Ulama
Hanafiyah menetapkan bahwa ijma’ itu dijadikan sebagai hujjah.
Mereka menerima ijma’ qauli dan ijma’ sukuti. Mereka
menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu
urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat
hukum baru adalah menyalahi ijma’. Ada tiga alasan dalam
menerima ijma’ sebagai hujjah yaitu:
a) Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang
timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah
sering memanggil para sahabat untuk memanggil para sahabat
untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila
dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan maka Umar
pun melaksanakannya.
b) Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan yang telah
diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang
ganjil dan tidak dipandang menyalahi aturan hukum. Imam
Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah di
fatwakan oleh ulama-ulama Kufah.
c) Adanya sebuah hadits yang menunjukkan keharusan
menghargai ijma’ seperti:
ن ال ه ل ل ه ل م م ام م ه .حم م ن ل لنل م فم ه م حم م
“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka
dianggap baik pula di sisi Allah SWT”.23
Dengan demikian jelaslah bahwa ulama Hanafiyah
menetapkan bahwa ijma’ merupakan satu di antaranya hujjah
22
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 162. 23
M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
Cet. ke-5, hlm. 153.
50
dalam beragama, yang merupakan hujjah qath’iyyah. Mereka
tidak membedakan antara macam-macam ijma’, oleh karena itu
apapun bentuk kesepakatan para ulama itu berhak atas
penetapan hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum24
.
d. Al-Qiyas
Al-Qiyas adalah “Penjelasan dan penetapan suatu hukum
tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang
jelas hukumnya dalam kitabullah, sunnah ataupun ijma’ karena
kesamaan illat”25
. Yang menjadi pokok pegangan dalam
menjalankan qiyas adalah bahwa segala hukum syara’ ditetapkan
untuk menghasilkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun
di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian-pengertian
dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan baik yang
diperintah maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan maupun
yang dimakruhkan, semuanya demi kemaslahatan ummat26
.
Walaupun demikian, tidak berarti semua masalah yang baru
timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur‟an , al-Sunnah dan
ijma’ boleh di qiyaskan begitu saja atas dalih kemaslahatan umum,
ada beberapa syarat dan rukun yang harus di penuhi untuk
melakukan qiyas, antara lain:
1. Ashal, yaitu sesuatu yang sudah dinashkan hukumnya yang
menjadi tempat mengqiyaskan atau dalam istilah ushul disebut
al-ashli (al maqis alaih).
2. Cabang (furu’), yaitu sesuatu peristiwa yang tidak ada nashnya
dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan
24
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 163. 25
Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: PT.
Al- Ma‟arif, 1997), hlm. 66. 26
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 164
51
hukumnya dengan ashalnya, atau dalam istilah ushul disebut
juga al-maqis.
3. Hukum Ashal, yaitu hukum syara’ yang dinashkan pada pokok
yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.
4. Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan
atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum, dan
illat inilah yang menjadi titik tolak serta pijakan dalam
melaksanakan qiyas27
.
d) Al-Istihsan
Al-Istihsan merupakan pola istinbath hukum Imam Abu
Hanifah, istihsan secara terminologi difahami dengan pindahnya
para fuqaha dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi
(tersembunyi)28
. Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum
dengan istihsan tapi tidak memberikan penjelasan bagaimana
sesungguhnya maksud dari pada tulisan istihsan tersebut. Ketika
menetapkan hukum dengan cara istihsan, beliau hanya mengatakan
“astahsin” artinya saya menanggap baik29
. Imam Abu Hanifah
beserta pengikutnya membagikan teori istihsan ini kepada enam
bentuk, yaitu:
1. Istihsan bi al-Nash, yaitu yang berdasarkan ayat atau hadits,
maksudnya ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus
yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum,
2. Istihsan bi al-Ijma’, yaitu istihsan yang berdasarkan pada ijma’,
maksudnya meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada
suatu kasus karena adanya ijma’,
3. Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi, istihsan ini memalingkan suatu
masalah dari ketentuan hukum qiyas jali kepada qiyas khafi,
27
Nazar Bakri, Fiqih dan Ushul Fiqh, (Bandung: Rajawali Press, 1993), hlm. 47. 28
Romli, Muqaranah Mazahib fi Al-Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999),
hlm. 79. 29
Iskandar Usman, Istihsan dan Pemahaman Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1994), hlm. 6.
52
tetapi keberadaannya lebih tepat untuk diamalkan, misalnya
wakaf dalam pertanian.
4. Istihsan bi al-Maslahah, yaitu istihsan yang berdasarkan
kepada kemaslahatan.
5. Istihsan bi al-‘Urf, yaitu terhadap ketentuan hukum yang
bertentangan dengan qiyas karena adanya ‘urf yang biasa
dipraktekkan oleh masyarakat.
6. Istihsan bi al-Dharurah, yaitu istihsan yang berdasarkan
keadaan darurat, maksudnya karena adanya keadaan darurat
yang menyebabkan seorang mujtahid untuk memberlakukan
kaidah umum atau qiyas.
e. Al-„Urf
Kata ‘urf secara terminologi berarti “Sesuatu yang
dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara
terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan
adalah:
ل حم م ال ل ل ل فم ل ل م ل ل ل ل م مال م ه ال ه ل م م ه م ل م اه ه م م ام م م ل ل ل
“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat
karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan
kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun
perbuatan”30
.
Istilah „urf dalam pengertian tersebut sama dengan
pengertian al-‘adah (adat istiadat). Seluruh ulama mazhab
termasuk Imam Hanafi menerima dan menjadikan ‘urf sebagai
dalil syara‟ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash
menjelaskan suatu masalah yang di hadapi. Adapun ‘urf yang
dijadikan sebagai hujjah adalah ‘urf yang tidak bertentangan
dengan syara‟, baik berupa perkataan dan perbuatan maupun ‘urf
yang menyangkut kebiasaan yang bersifat umum dan khusus atau
30
Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153.
53
biasa disebut dengan ‘urf shahih (yaitu ‘urf yang tidak
bertentangan dengan syari‟at)31
.
5. Karya Imam Abu Hanifah
Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberi fatwa, Imam
Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagaian ide
dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan
dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab
yang dituliskan sendiri antara lain:
1. Al-fara’id : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala
ketentuan menurut hukum Islam.
2. Asy-syurut : yang membahas tentang perjanjian.
3. Al-fiqh al-akbar : yang membahas tentang ilmu kalam atau teologi dan
memberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Manshur Muhammad Al-
Maturidi dan Imam Abu Al-Muntha Al-Maula Ahmad bin Muhammad
Al-Maghnisawi.
Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak,
didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Imam Abu Hanifah. semua
kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut Mazhab Imam Hanafi. Ulama
Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab kepada tiga tingkatan.
Pertama, tingkat masail-masail al-Ushul (maslah-masalah pokok),
yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang
diriwayatkan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, kitab dalam kategori
ini biasanya disebut Zahir ar-Riwayah, (teks riwayat) yang terdiri atas
lima kitab yaitu:
Al-mabsuth : (Syamsuddin Al-Syarkasyi).
Al-jami’ as-Shagir : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
Al-jami’ al-Kabir : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
As-sair as-Saghir : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
31 Nasroen Harun, Ushul Fiqh, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 142.
54
As-sair al-Kabir : (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
Kedua, tingkat masail an-Nawazir (masalah yang diberikan sebagai
nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini
adalah:
Haran-Niyah : ( niat yang murni)
Jurj an-Niyah : ( rusaknya hati )
Qais an-Niyah : ( kadar hati )
Ketiga, tingkat al-Fatwa wa al-Faqi’at. (fatwa-fatwa dalam
permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqih
yang berasal dari istimbath (pengambilan hukum dan penetapannya)
ini adalah kitab-kitab an-Nawazil (bencana), dari Imam Abdul Lais as-
Samarqandi32
.
Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada
kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa
manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam
pandangan syari‟at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia
sangat ektrim menilainya sehingga beranggapan Imam Abu Hanifah
mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW.
Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Mereka beranggapan bahwa
beliau telah keluar dari agama. Perbedaan pendapat yang ektrim dan
bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana
Imam Hanafi hidup. Orangorang pada waktu itu menilai beliau
berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang
kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara
maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang
lain33
. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun
tepatnya pada bulan rajab
32
Abdul Aziz Dahlan Dkk, Ensik Lopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru
Van Hoeve,1996), cet ke-1, hlm. 81. 33
Abdurahman Asy-Syarqawi, Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan Lima
Imam Mazhab Terkemuka, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet ke-1, hlm. 49.
55
B. Imam Syafi’i
1. Biografi Imam Syafi’i
Imam Syafi‟i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris
ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi‟i ibn As-Sa‟ib ibn „Ubaid ibn „Abd
Yazid Ibn Hasyim ibn „Abd Al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Gaza,
Palestina pada tahun 150 Hijriyah (767-820 M), berasal dari keturunan
bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh dari Rasulullah saw. Dari
ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga
Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib
r.a.34
Adapun dari pihak ibunya Imam Syafi‟i bin Fatimah binti Abdillah
bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal dengan
panggilan al-Syafi‟i karena dinisbat dari kakeknya yang ketiga yaitu syaf‟i
bin al-Sa‟ib.35
Karena Imam Syafi‟i ditinggal oleh bapaknya sejak bayi, maka
beliau diasuh oleh ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Setelah usia
Imam Syafi‟i 2 tahun, ia dibawa oleh ibunya kembali ke Makkah al-
Mukarromah, yaitu kampung halaman beliau, dan tinggal di Makkah
sampai usia 20 tahun, yakni sampai tahun 170 H.36
Hal ini dilakukan agar
nasab al-Syafi‟i dapat tetap terjaga serta dapat berkumpul dengan keluarga
ibunya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Wahb :
مللمقي : هال لته بل ال م م ل مخم م ل ه يل م مى اضل فل مةل فم م م : فم ه ل ه ي مل ل ه الل ل ل : م م ل بل ل مهلبل م م ثفل م همل بلأمهل لكم فم مكه ل ه ل
Artinya : “Dari ibn Wahb, ia (telah) berkata, saya (telah) mendengar al-
Syafi’i berkata: Aku dilahirkan di Yaman, ibuku khawatir kehilangan
34
Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), cet ke-I, hlm. 118 35
Edy Setyawan, Perbandingan Madzhab (ikhtiar Dinamisasi Pemahaman Fikih
Modern), (Cirebon; CV Hikmah, 2010) cet ke-I, hlm. 85-86 36
Siradjuddin, Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta;
Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), cet ke-XV, hlm.21
56
(nasab), maka ia berkata engkau harus bergabung dengan keluargamu
agar menjadi seperti mereka.”37
Imam Syafi‟i lahir pada zaman Bani Abas, tepatnya pada
kekuasaan Abu Ja‟far, Al Manshur (137-159 H/754-774 M) sampai
Khalifah Al Makmun (198-218 H/813-833 M). Sejak usia sembilan tahun
ia telah hafal al-Qur‟an dan banyak Hadits. Setelah beliau berumur 15
tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan member
fatwa kepada khalayak ramai. Beliau pun tidak keberatan menduduki
jabatan guru besar dan mufti di dalam masjid Al Haramdi Mekkah dan
sejak saat itulah beliau terus member fatwa. Tetapi walaupun demikian
beliau tetap belajar ilmu pengetahuan di Mekkah.38
Pada usia 20 tahun, ia
pergi ke HIjaz untuk belajar hadits dan fiqh kepada Imam Malik,
kemudian pergi ke Irak untuk mempelajari fiqh kepada murid-muridnya
Abu Hanifah. Ia pernah melawat ke Yaman dan mengajar di sana. Harun
Al-Rasyid pernah mendengar kehebatan beliau, kemudian dipanggil ke
Baghdad untuk mengajar. Di Baghdad inilah, beliau mengeluarkan qaul
Qadim-nya. Kemudian ia hijrah ke Mesir dan mengajar di masjid Amru
bin Ash. Di Mesir beliau merevisi pemikirannya yang disebut qaul
Jadid.39
Pada usia 30 tahun, Imam Syafi‟i menikah dengan seorang wanita
dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi‟ seorang putrid dari keturunan
khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari
pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki dan
dua orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad
bin Syafi‟i yang menjadi qadhi di jazirah Arab (w.240 H). setelah 6 tahun
tinggal di Mesir mengembangkan madzhabnya dengan jalan lisan dan
37
Ibn Hajar al-Asqalani, Tahzib al-Tahzib juz VII, (Beirut Dar al-Fikr, 1995),
hlm. 24 38
M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1995), hlm. 205 39
Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok;
Gramedia Publishing, 2010), hlm. 122
57
tulisan dan sesudah mengarang kitab Ar-Risalah (dalam ushul fiqh) dan
beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia pada tahun 204 H, pada usia 54
tahun, bertepatan dengan 28 Juni 819 M.40
2. Pendidikan Imam Syafi’i
Sejak dini, pada diri Imam Syafi‟i telah nampak bakat yang luar
biasa untuk menjadi seorang ilmuwan. Masa kanak-kanak dan masa
remaja dilalui Imam Syafi‟i dibawah asuhan ibunya dalam lingkungan
Bani Muthalib. Sesuai dengan tujuan kepindahannya ke Mekkah, masa ini
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan, pembentukan
pribadi dan penguasaan ilmu pengetahuan.
Pendidikan Imam Syafi‟i diawali dengan belajar al-Qur‟an.
Dengan usaha dan bimbingan ibunya, Imam Syafi‟i telah menghapal al-
Qur‟an dalam usia yang masih sangat muda.41
Karena kecerdasan otaknya
yang ditopang dengan kemauan keras membuat Imam Syafi‟i mampu
menguasai berbagai cabang ilmu (terutama ilmu agama) dengan baik.
Bahkan beliau mampu menghapal semua pelajaran yang sedang didiktekan
pada anak-anak yang lain.42
Pelajaran bacaan al-Qur‟an diperolehnya dengan rangkaian sanad
dari Ismail ibn Qastantin dari Syibl, dari Abdullah ibn Katsir dari Mujahid
dari Ibnu „Abbas dari Ubay ibn Ka‟ab dari Rasulullah SAW. Setelah itu, ia
melengkapi ilmunya dengan mempelajari bahasa dan sastra Arab. Untuk
itulah ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan suku Hudzail, suku
bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syafi‟i
secara berkelanjutan selama dua puluh tahun.43
40
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 108-110. 41
Menurut al-Muzanni, al-Syafi‟i pernah menyatakan bahwa ia telah menghapal
al-Qur‟an ketika berumur tujuh tahun. Tahzib al-Tahzib juz VII, hlm 25 42
Imam al-Syafi‟i, Ikhtilaf al-Hadis, (Beirut : Muassasah al Kutub al Tsaqafiyyah
,1985), hlm. 20 43
Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. Ushul Fiqh, terj. Zaid H. al- Hamid,
(Pekalongan Raja Murah, 1992), hlm. 252
58
Setelah itu, Imam Syafi‟i pun kemudian memusatkan perhatian
pada pelajaran hadis. Pada masa Imam Syafi‟i menjalani pendidikan
awalnya, khususnya di Mekkah dan Madinah, al-Qur‟an dan hadislah yang
menjadi tumpuan bagi hampir semua ilmu pengetahuan umat waktu itu.
Bahkan, seseorang hanya akan dianggap sebagai alim bila ia menguasai
banyak pengetahuan tentang keduanya karena kata ilmu ketika itu
digunakan untuk menyebutkan kedua pengetahun tersebut.44
Imam Syafi‟i mempelajari hadits dari dua tokoh ahli hadits yang
ada di Hijaz yaitu Sufyan ibn Uyainah yaitu seorang ahli hadits Mekkah
dan Malik ibn Anas seorang ahli hadits Madinah.45
Dengan kekuatan
ingatan yang sebelumnya telah terlatih menghapal al-Qur‟an dan syair-
syair, sangat mendukung keberhasilannya dalamk menghapal hadits-hadits
yang diajarkan oleh gurunya.
Setelah menghapal al-Qur‟an, hadits dan bahasa, Imam Syafi‟i pun
kemudian mulai mempelajari fikih. Ketiga ilmu yang telah dipelajari
sebelumnya tersebut sangat membantu beliau dalam penguasaan tafsir dan
hadits-hadits hukum yang sangat penting sebagai bahan kajian dan
sandaran fatwa dalam ilmu fikih. Dan dengan kecerdasannya tersebut, ia
segera menguasai metode istinbath aliran ahl al-hadits. Pelajar fikih mula-
mula ia peroleh dari Muslim ibn Khalid al-Zanji yaitu seorang mufti.
Disamping itu, Imam Syafi‟i juga mempelajari fikih dari ulama
Hijaz lainnya yang terkenal sebagai pusat fikih ahl al-hadits yaitu Imam
Anas ibn Malik di Madinah. Bahkan, sebelum datang menghadap sang
imam, Imam Syafi‟i telah menghapal kitab al-Mawathttha yang
merupakan kitab fikih berdasarkan hadits yang disusun oleh Imam Anas
ibn Malik. Pada tahun 179 H, Imam Malik meninggal dunia. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap proses pendidikan Imam Syafi‟i. Beliau mulai
44
Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i,
(Bandung Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 31-32 45
Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. Ushul Fiqh, terj. Zaid H. al- Hamid,
(Pekalongan Raja Murah, 1992), hlm. 252
59
memikirkan sumber penghidupannya. Atas bantuan orang-orang Quraisy,
ia diterima oleh wali negeri Yaman yang sedang berkunjung ke Madinah
untuk kerja di wilayahnya.46
Akan tetapi, periode bekerja di Yaman ini tidak berlangsung lama.
Sebab, tidak lama kemudia ia dituduh trelibat dalam kegiatan politik
kelompok ‘Alawi, yaitu partai oposisi bani „Abbas, sehingga ia dikirm ke
Baghdad untuk diinterogasi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun,
berkat kecerdikannya ia bisa bebas dari tuduhan.47
Kehadirannya di ibu kota itu memberinya kesempatan baik untuk
berkenalan dan belajar dengan tokoh ulama Hanafiyah. Di Baghdad inilah
al-Syafi‟i berjumpa dengan sejumlah ulama, sahabat dan murid Imam Abu
Hanifah seperti Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani.48
Dengan al-
Syaibani inilah Imam Syafi‟i mempelajari pokok-pokok pikiran madzhab
Hanafi serta membaca dan menelaah berbagai kitan ulama Irak dan
membandingkannya dengan pola pemikitan ulama Hijaz. Dengan
demikian, Imam Syafi‟i dapat melihat dengan jelas semua kelebihan dan
kelemahan yang terdapat pada kedua aliran tersebut.
Era Imam Syafi‟i memang merupakan era berkembangnya
pemikiran fikih secara luas dan mendalam. Tidak heran, bahwa beliau
mempunyai wawasan yang luas dan analisa yang tajam terhadap berbagai
masalah hukum. Sehingga, ia mengerti letak kelemahan dan keuatan, luas
dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab yang ada. Setelah
belajar di Baghdad selama dua tahun lamanya, Imam Syafi‟i kembali ke
Mekkah sebagai ulama besar. Ia mengajar di masjid al-Haram dan
berdiskusi dengan para ulama yang banyak datang ke sana teruatama pada
46
Ahmad Nahrawi, al-Syafi’i fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid, hlm. 58 47
Dede Rosyadan, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta. Raja Grafindo
Persada 1996), hlm. 149 48
Romli SA, Muqaranah Madzhab fi al-Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1999), hlm. 27
60
musim haji.49
Tidak kurang sembilan tahun lamanya Imam Syafi‟i
menetap di Mekkah dan selama ini pila beliau berhadapan dengan
persoalan-persoalan yang beragam yang tidak jarang melahirkan
perbedaan satu sama lainnya. Namun, dengan modal pengetahuan yang
luas dan dalam terhadap fikih dari berbagai sumber-sumber seperti
Mekkah, Mdinah, Yaman dan Irak beliau dapat menelaah berbagai
pendapat tersebut dan mengadakan penilaian, bahkan menyusun kaidah-
kaidah untuk menjadi dasar bagi madzhab baru yang akan dibangunnya
diantaranya kedua aliran ahl al-hadits dan ahl al-ra’yu.
Dengan kata lain, Imam Syafi‟i mulai melakukan perbandingan
dan berusaha membuat metode atau kaidah-kaidah istinbath tersendiri
setelah menelaah berbagai persoalan dari dua corak pemikiran fikih yang
berbeda yang telah ada sebelumnya dan mempelajari dasar-dasar
pijakannya masing-masing. Corak pemikiran hukum yang dirumuskan
Imam Syafi‟i memang berbeda dengan yang sudah ada. Perbedaan ini
bersifat fundamental, karena itu tidak dapat disejajarkan dengan madzhab-
madzhab terdahulu.50
Periode mengajar di Mekkah, merupakan penyempurnaan kegiatan
belajar Imam Syafi‟i, dismaping itu pula, masa ini juga mempunyai arti
yang penting bagi persiapan lahirnya madzhab Imam Syafi‟i. karena,
tanggung jawab sebagai pengajar dan juga kegiatannya dala diskusi-
diskusi dengan ulama yang datang ke Mekkah merupakan salah satu faktor
yang penting bagi perkembangan pemikiran hukum Imam Syafi‟i.
49
Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 22 50
Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, diterjemahkan oleh Agah
Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 167
61
3. Guru dan Murid Imam Syafi’i
a. Guru-guru Imam Syafi’i
Imam Syafi‟i mempelajari ilmu tafsir, fiqih dan hadits
kepada banyak guru, yang negerinya antara satu dengan yang lain
berjauhan.
1) Di Mekkah
Muslim bin Khalid al-Zanji, Sufyan bin „Uyainah, Sa‟ad
bin Abi Salim al Qaddah, Daud bin „Abd al-Rahman al-„Athar,
„Abd al-Hamid bin „Abd al-„Aziz bin Abi Zuwad, Isma‟il bin
Qusthantein.
2) Di Madinah
Imam Malik bin Anas (pembangun mazhab Maliki),
Ibrahim Ibnu Sa‟ad al-Anshari, Abdul „Aziz bin Muhammad
al-Dahrawardi, Ibrahim Ibnu Abi Yahya al-Islami, Muhammad
bin Sa‟id, Abdullah bin Nafi‟.
3) Di Yaman
Muharraf bin Mazim, Hisyam bin Abi Yusuf, Umar bin Abi
Salamah (pembangun mazhab al-Auza‟i), Yahya bin Hasan
(pembangun mazhab Laits)
4) Di Iraq
Waki‟ bin Jarrah, Humad bin Usmah, Isma‟il bin Ulyah,
Abdul Wahab bin abdul Madjid, Muhammad bin Hasan, Qadhi
bin Yusuf.
Demikian daftar nama-nama guru Imam Syafi‟i. dari nama-
nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi‟i telah
menghimpun fiqh ahli Mekkah, Fiqih Madinah, Fiqih Yaman, dan
Fiqih Iraq.51
51
Siradjuddin, Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta;
Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), cet ke-XV, hlm.153-154
62
b. Murid-murid Imam Syafi’i
1) Murid-murid Imam Syafi‟i di Baghdad
Murid-murid Imam Syafi‟i di Baghdad banyak sekali, tetapi
yang besar-besar yang menjadi penyambung lidah utama dari
Imam Syafi‟i adalah Abu Ali al Hasan as Shabah az Za‟faran,
(wafat 260 H), Husein bin „Ali al Karabisi, (wafat 240 H), Imam
Ahmad Hanbal, (wafat 240 H), Abu Tsur al Kalabi, (wafat 240 H),
Ishak bin Rahuyah, (wafat 277 H), Ar Rabi‟ bin Sulaiman al
Muradi, (wafat 270 H), Abdullah bin Zubair al Humaidi, (wafat
219 H), Ibn Hanbal al Buthi, Al-Muzani, Abd „Ubaid Al-Qasim
Ibn Salam Al-Luqawi.52
2) Murid-murid Imam Syafi‟i di Mesir
Mereka adalah Ar-Rabi‟i bin Sulaiman al Muradi yang
datang bersama-sama Imam Syafi‟i dari Baghdad, (wafat 270 H),
Abdullah bin Zuber al Humaidi, yang juga datang bersama beliau
dari Baghdad (wafat 219 H), Al Buwaithi nama lengkapnya Abu
Yak‟ub Yusuf Ibnu Yahya al Buwaithi (wafat 232 H), Al Muzany,
nama lengkapnya Abu Ibrahim Isma‟il bin ahya al Muzani (wafat
264 H), Al Rabi‟i bin Sulaeman al Jizi (wafat 256 H), Harmalah
bin Yahya al Tujibi (wafat 243 H), Yunus bin Abdil A‟ala (wafat
264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 268
H), Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 268 H),
Abu Bakar al Humaidi (wafat 129 H), Abdul Aziz bin Umar (wafat
234 H), Abu Utsman Muhammad bin Syafi‟i (anak kandung Imam
Syafi‟i) (wafat 232 H), Abu Hanifah al Aswani orang Mesir berasal
dari Qibth (wafat 271 H), dan lain-lain.
52
Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 257.
63
4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i
Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu
hukum, Imam Syafi‟i memakai empat dasar yaitu: al- Quran, al-Sunnah,
Ijma‟ dan qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitabnya, al-
Risalah sebagai berikut:
محم ل ل م ل فم ه لمم م ام ل م ل رممن حل ل م ل : م ل ل بم ل ل الكل م بل ل ل ل ل مةل ل حم ا لنلةل م ل ل م ال ل لمل م ل مةل للمبمل ل ال ل م ال الل لم ال م ل
Artinya: “Tidaklah seorang mengatakan dalam hukum selamanya ini
halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan
itu adalah kitab suci al-Qur‟an, al-Sunnah, al-Ijma‟, dan al- Qiyas.”
Adapun penjelasan dari masing-masing pokok pegangan yang
digunakan Imam Syafi‟i dalam membina madzhabnya adalah sebagai
berikut:
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an adalah lafadz Arab yang diturunkan kepada
Sayyidina Muhammad SAW. Untuk direnungkan dan diingat, yang
diriwayatkan secara mutawatir. Mulai dengan surat al-Fatihah dan
diakhiri dengan surat al-Nas bahasa Arab adalah bagian dari keaslian,
terjemahanya tidak dikatakan al-Qur‟an sehingga apabila seseorang
membaca terjemahnya dalam sholatnya tidaklah sah.53
Para ulama
sepakat menetapkan bahwa al-Qur‟an adalah sumber pertama segala
sumber hukum Islam. Mereka berselisih pendapat, hanya tentang
kedudukan al-Sunnah, apakah dia dapat mendatangkan hukum-hukum
yang tidak ada pokoknya dalam al-Qur‟an ataukah tidak, Imam Syafi‟i
menegaskan bahwa al-sunnah berhak mendatangkan hukum yang tidak
ada pokoknya dalam al-Qur‟an.54
Imam Syafi‟i mengkaji al-Qur‟an secara mendalam dan
mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur‟an ke dalam bentuk „amm dan
53
Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. Ushul Fiqh, terj. Zaid H. al- Hamid,
(Pekalongan: Raja Murah, 1992), hlm. 50. 54
M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
Cet. ke-5, hlm. 277.
64
khas, beliau juga mengatakan bahwa di dalam al- Qur‟an ada
pernyataan-pernyataan tertentu yang bersifat umum di dalam al-Qur‟an
yang mengandung sebagai pernyataan „amm dan khas. Karena
kedudukan al-Qur‟an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi
penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum
suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari
jawaban penyelesaian dari al-Qur‟an, selain hukumnya dapat
disesuaikan dengan al-Qur‟an maka ia tidak boleh mencari jawaban
lain di luar al-Qur‟an.55
b. Sunnah
Sandaran kedua dari madzhab Syafi‟i adalah sunnah.
Menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari sunnah selama
sunnah masih ada, mengenai hadits ahad, Imam Syafi‟i tidak
mewajibkan syarat kemasyhuran sebagaimana yang berlaku pada
madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan
oleh Imam Maliki, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya.
Menurut Imam Syafi‟i hadits itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap
cukup, baginya hadits ahad tidak masalah untuk dijadikan sandaran,
selama yang meriwayatkannya dapat dipercaya, teliti, dan selama
hadits itu muttasil (sanadnya bersambung) kepada Rasulullah. Jadi
beliau tidak mengharuskan hanya mengambil hadits mutawatir saja.56
Imam Syafi‟i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan
sebagai berikut:
Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang
tidak terpercaya.
Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
Perawinya dhabit (kuat ingatannya)
55
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73 56
Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), hlm. 116
65
Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang
yang menyampaikan kepadanya.
Perawi itu tidak menyalahkan para ahli ilmu yang juga
meriwayatkan hadits itu.57
Imam Syafi‟i menempatkan as-sunnah sejajar dengan al-
Qur‟an, karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan al-Qur‟an dan
hadits mutawatir. Disamping itu, al-Qur‟an dan sunnah keduanya
adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat
seperti al-Qur‟an. Mengenai kedudukan as-sunnah Imam Syafi‟i
mengungkapkan bahwa kedudukan sunnah terhadap al-Qur‟an adalah
sebagai berikut :58
Menerangkan kemujmalan al-Qur‟an, seperti menerangkan
kemujmalan ayat tentang shalat dan puasa.
Menerangkan khash al-Qur‟an yang dikehendaki „amm dan „amm
yang dikehendaki khas.
Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur‟an.
c. Ijma‟
Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan ijma‟
menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur‟an dan
sunnah, berarti ijma‟ dapat menetapkan hukum yang mengikat dan
wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam
al-Qur‟an maupun sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur
mengemukakan beberapa ayat al-Qur‟an diantaranya adalah surat an-
Nisa ayat 115,59
adalah sebagai berikut:
57
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 129 58
M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
Cet. ke-5, hlm. 250-251 59
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 73
66
Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul Rasul sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang
bukan jalan orang-orang mu‟min, kami biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami
masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-
buruk tempat kembali. (Q.S. an-Nisa: 115)60
Dalam ayat di atas “jalan-jalan orang mukmin” diartikan
sebagai apa-apa yang disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah
yang disebut ijma‟ kaum mukminin.61
Imam Syafi‟i mengatakan,
bahwa ijma‟ adalah hujjah dan ia menempatkan ijma‟ ini sesudah al-
Qur‟an, as-sunnah sebelum qiyas.62
Ijma‟ yang dimaksudkannya ialah
suatu hasil kesepakatan para sahabat secara integral mengenai hukum
suatu masalah. Kesepakatan ini harus diperoleh secara jelas. Ijma‟
yang dipakai Imam Syafi‟i sebagai dalil hukum itu adalah ijma‟ yang
disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah
SAW. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma‟ yang berstatus dalil
hukum itu adalah ijma‟ sahabat.63
Imam Syafi‟i hanya mengambil
ijma‟ sharih yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum
suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mereka mengemukakan
pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hakim.
Maksudnya bahwa setiap mujtahid, mengeluarkan pernyataan
atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas sebagai
60
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur‟an, 1971), hlm. 140-141 61
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 118 62
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 130 63
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 103
67
dalil hukum dan menolak ijma‟ sukuti yaitu sebagian dari mujtahid
suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai
suatu kasus, baik melalui fatwa atau suatu putusan hukum, dan sisa
dari mereka tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut,
baik merupakan persetujuan terhadap pendapat yang telah
dikemukakan atau menentang pendapat itu menjadi dalil hukum.
Alasannya menerima ijma‟ sharih karena kesepakatan itu disandarkan
kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas
sehinnga tidak mengandung kerugian mujtahid. Diamnya sebagian
mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.
Adapun yang pertama, yaitu ijma‟ sharih, maka itulah ijma‟
hakiki, dan ini merupakan hujjah syar‟iyah dalam madzhab jumhur
ulama, sedangkan yang kedua yaitu ijma‟ sukuti, maka ia adalah ijma‟
I’tbar (anggapan) karena sesungguhnya orang yang diam saja tidak ada
kepastian bahwa ia setuju. Oleh karena itu, tidak ada kepastian
mengenai terwujudnya kesepakatan dan terjadinya ijma‟ dan karena
inilah, ia masih dipertentangkan kehujjahannya, jumhur ulama
berpendapat bahwa ijma‟ sukuti bukanlah hujjah. Bahwa ijma‟ tersebut
tidak lebih dari keadaannya sebagai pendapat dari individu para
mujtahid. Dalam definisi ijma‟64
menurut Imam Syafi‟i adalah
kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar
terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin, oleh karena ijma baru
masyarakat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka
dengan gigih Imam Syafi‟i menolak ijma penduduk Madinah (amal
ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari
ulama mujtahid yang ada pada saat itu.65
d. Qiyas
64
Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ijma‟ Menurut Istilah Para Ahli Ushul Fiqh
adalah: Kesepakatan para Mujtahid Dikalangan Umat Islam pada Suatu Masa Setelah
Rasulullah SAW Wafat atas Hukum Syara‟ Mengenai suatu Kejadian. Abd al-Wahhab
Khalaf, Ilm Usul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam 1978), hlm. 45. 65
Imam Syafi‟i, al-Risalah, (Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H), hlm. 32
68
Dari segi bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu atas lainnya
dan mempersamakannya.66
Sedangkan menurut istilah ahli ushul ialah:
م لرل لللم اه م لرل مل آ ل م ل ال ل لةل فم م ل م ل ل للهكل مل ل م ال ل خمرم ل للهكل
Artinya: “Menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada
orang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang
menyebabkan hukumnya juga sama.”67
Sesuai dengan ta’rif tersebut di atas, apabila ada suatu
peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan illat
hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui
illat-illat hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang
hukumnya adalah sama dengan illat hukum dari peristiwa yang sudah
mempunyai nash tersebut, maka peristiwa yang tidak ada nashnya ini
disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nashnya, lantaran adanya
persamaan illat hukum pada kedua peristiwa itu tidak akan ada
sekiranya tidak ada illat-illatnya.68
Pendirian Imam Syafi‟i tentang hukum qiyas sangat hati-hati
dan sangat keras, karena menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan
itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan
memaksa, berikut beberapa perkataan beliau tentang hukum qiyas.69
Imam Ahmad Ibn Hambal pernah berkata: “Saya pernah berkata
kepada Imam Syafi‟i tentang hal qiyas, maka beliau berkata: “Di
kala keadaan darurat.” Artinya, bahwa beliau mengadakan
hukum secara qiyas jika memang keadaan memaksa.
66
Hanafie, Ushul Fiqh, (Jakarta: Widjaya, 1989), hlm. 128 67
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 200. 68
Muctar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: al-
Maarif, 1997), hlm. 66 69
Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm. 209.
69
Imam Syafi‟i pernah berkata: “Saya tidak akan meninggalkan
hadits Rasul karena akan memasukkan hukum qiyas, dan tidak
ada tempat bagi qiyas beserta sunnah Rasulullah.”
Selanjutnya beliau berkata: “Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi
perintah Rasulullah tentulah jatuh dengan sendirinya dan tidak
akan dapat berdiri tegak, juga qiyas tidak akan dapat tegak
selama ada sunnah.”
Selain daripada itu hukum qiyas yang terpaksa diadakan adalah
hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada
pokoknya tidak dapat dipikirkan sebabsebabnya seperti, ibadah shalat
dan puasa. Oleh karena itu beliau berkata: “Tidak ada qiyas dalam
hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan
ibadah itu telah cukup sempurna dari al-Qur‟an dan as-Sunnah.” Dari
uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa cara Imam Syafi‟i
mengambil atau mendatangkan hukum qiyas itu adalah sebagai
berikut:
Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau muamalat saja.
Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari
nash al-Qur‟an atau dari hadits yang shahih.
Cara beliau mengqiyas adalah dengan nash-nash yang tertera
dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan dari hadits Nabi.
Oleh sebab itu Imam Syafi‟i tidak sembarangan mendatangkan
atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan beberapa
peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil)
dengan cara qiyas, sebagai dalil penggunaan qiyas, beliau
mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur‟an surat an-Nisa ayat
59.70
70
Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, hlm. 131
70
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al- Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa‟: 59).71
Rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut:56
Al-Ashlu, yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya, ia disebut
juga maqis‟alah (yang diqiyaskan kepadanya), mahmul‟alaih
(yang dijadikan pertanggungan), dan musyabbah bih (yang
diserupakan dengannya).
Al-Far’u, yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya, ia juga
disebut: al-Maqis (yang diqiyaskan), al-Mahmul (yang
dipertanggungjawabkan), dan al-Musyabbah (yang
disempurnakan).
Hukum Ashl, yaitu: hukum syara‟ yang ada nashnya pada al-
ashl (pokok), dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada
al- Far’u (cabangnya).
Al-Illat, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk
membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya kebenaran
sifat itu pada cabang (far‟u), maka ia disamakan dengan
pokoknya dan segi hukumnya.
71
Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pusaka
Agung Harapan, 2006), hlm. 80
71
5. Karya Imam Syafi’i
Kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi‟i ketika di Mesir,
di antaranya Ar Risalah dalam ilmu ushul fiqih, Kitab Ahkamil Qur’an,
Kitab Ikhtilafi Hadits, Kitab Ibtalul Istihsan, Kitab Jima’ul ‘Ilmi, Kitab
Al-Qiyas, Kitab Al-‘Umm dalam ilmu fiqih, Kitab Al Musnad, Kitab Al
Mukhtasar Al Muzani, Kitab Harmalah, Kitab Jami’al Muzani al
Kabir, Kitab Jami’al Muzani as Sagir, Kitab Istiqbalul Qibiatain,
Kitab Mukhtasar al Buwaithi, Kitab Al Amali, Kitab al Qassamah,
Kitab Al Jizyah, Kitab Qital Ahlil Bagyi.72
72
Siradjuddin, Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta;
Pustaka Tarbiyah Baru, 2007), cet ke-XV, hlm. 182