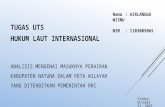Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan - Final
-
Upload
bustanulmutaallimin -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan - Final
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
alam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan acapkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa
sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.1 Dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan berkembang dan berkembang terus, sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita rugi, maka garis hidupnya menurun. Jadi garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik. Sebagian perusahaan dapat mempertahankan hidupnya, tetapi sebagian tidak dapat mempertahankan lagi hidupnya, akhirnya perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar. Dalam rangka pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini disebut perusahaan yang solvabel, artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya.2 Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut Insolvensi, artinya tidak mampu membayar. Istilah hukum Insolvensi menunjukkan pada suatu kumpulan dari aturan-aturan yang mengatur hubungan debitor (yang berada dalam
1 Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan
di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1. 2 Ibid.
D
Bab I. Pendahuluan
2
kesulitan pembayaran akibat ketidakmampuan finansial) dengan para kreditornya.3 Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, yang mengakibatkan Indonesia telah mengalami krisis kepercayaan khususnya terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang menuju suatu kehancuran akibat krisis ekonomi yang diawali oleh krisis nilai tukar. Krisis tersebut telah menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam, dan kemudian berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar.4 Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-undang Kepailitan yang ada. Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada “tekanan” dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.5 Indonesia memang tidak dapat mengelak desakan IMF yang seolah-olah mendikte tersebut. Setelah Indonesia hampir bangkrut karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, IMF bagaikan dewa penolong yang
3 Mr. J.B. Huizink, 2004, Alih Bahasa Linus Doludjawa, Insolventie, Pusat Studi Hukum dan ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 21.
4 Sitompul Zulkarnain, 2002, Perlindungan Dana Nasabah: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 2.
5 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, Cetakan Ketiga, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
3
memberikan setetes air di tengah padang kehausan. Namun untuk dapat menikmati bantuan IMF ini Indonesia mau tidak mau harus mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF agar bantuan (baca: utang) tersebut mengucur ke Indonesia. Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrukan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur dalam Faillisements-Verordening (Undang-undang Kepailitan Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). Dalam masa-masa tersebut, hingga dilakukannya revisi atas Undang-undang Kepailitan tersebut, urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurangpopuleran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu “persidangan” yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis berarti “hilangnya” hak-hak kreditur, atau bahkan “hilangnya” nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditur setuju dan bahkan akan berusaha keras untuk menentangnya. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya, Peraturan Kepailitan yang lama sebenarnya tidak berlaku untuk golongan rakyat pribumi. Undang-undang Kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Hal ini sesuai dengan Staatsblad 1924 No. 556 dan Staatsblad 1917 No. 129.
Bab I. Pendahuluan
4
Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Faillisements Verordening Stb 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pada tanggal 22 April 1998, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut kemudian selanjutnya menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Kemudian UU No. 4 Tahun 1998 direvisi kembali menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. yang telah disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004 (selanjutnya UU Kepailitan yang baru).6 Walaupun Draft Rancangan Undang-undang Kepailitan (RUUK) tersebut sebenarnya telah diserahkan Pemerintah sejak tahun 2001 akan tetapi RUUK tersebut baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI tersebut menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan RUUK tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi bukan Komisi II yang membidangi hukum.7 Seperti yang diduga, DPR tidak memberikan komentar yang berarti terhadap RUUK tersebut, dan cenderung hanya mengikuti draft-draft usulan yang diajukan oleh pemerintah. Walaupun revisi RUUK tersebut masih jauh dari yang diharapkan, akan tetapi banyak hal-hal yang baru dan cukup penting serta memberi ketegasan dalam Undang-undang Kepailitan yang baru (UU No. 37 Tahun 2004) tersebut dibandingkan dengan Undang-undang Kepailitan yang lama (UU No. 4 Tahun 1998), seperti contohnya defenisi utang, tentang kewenangan Pengadilan Niaga terhadap kewenangan arbitrase dan secara khusus berhubungan dengan topik ini, menegaskan ketidakberwenangan pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pailit kepada bank secara langsung dengan memberikan kewenangan kepada panitera untuk menolak mendaftarkan permohonan pailit tersebut. Sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan permasalahan permohonan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor kepada debitor bank seperti yang dimaksud dalam
6 Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 (merupakan ayat tambahan) berbunyi: “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.
7 Ricardo Simanjuntak, 2004, Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23- No. 3 – Tahun 2004, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 96.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
5
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, sama sekali tidak mengalami perubahan redaksi apalagi perubahan substansi. Yang berubah hanyalah kedudukan pasal. Dimana pada Undang-undang Kepailitan yang lama (UU No. 4 Tahun 1998) ketentuan tersebut terletak pada Pasal 1 ayat (3), sementara pada Undang-undang Kepailitan yang baru (UU No. 37 Tahun 2004) pasal tersebut berpindah ke Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi pada Pasal 6 ayat (3) nya, Undang-undang Kepailitan yang baru tersebut membangun satu saringan awal dengan memberikan kewenangan kepada Panitera untuk menolak permohonan pailit yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) tersebut pada saat diajukannya pendaftaran permohonan pailit. Dalam hal ini semakin jelas peletakan penentuan pailit tidak pailitnya bank berada di tangan Bank Indonesia. Masalah kepailitan menjadi suatu permasalahan yang serius, sejak kasus perusahaan Asuransi Prudential yang dengan gampang dipailitkan merupakan imbas lemahnya UU Kepailitan yang lama (UU No. 4 Tahun 1998). Putusan pailit yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Niaga terhadap Perusahaan Asuransi Prudential, yang notabene adalah perusahaan yang tergolong sehat mengundang pro-kontra berbagai pihak. Tak heran kalau kemudian suara-suara yang menuntut amandemen UU Kepailitan, yang jauh sebelumnya telah disuarakan kini semakin keras gaungnya. Perusahaan yang akan dipailitkan dapat diistilahkan pada kapal yang karam ditengah lautan yang diterjang oleh ombak dan badai, sehingga mengakibatkan kapal tersebut mengalami kerusakan. Melihat kondisi kapal yang telah rusak diambil suatu tindakan apakah kapal itu dipertahankan atau dihancurkan. Apabila kerusakan pada kapal tersebut sangat parah sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal maka sebaliknya kapal itu dibiarkan saja sehingga mengakibatkan kapal menjadi hancur (yang diistilahkan dengan pailit), sedangkan apabila kapal tersebut kerusakannya masih dapat ditanggulangi maka kapal itu diperbaiki agar dapat dipakai kembali (yang diistilahkan dengan reorganisasi). Demikian juga halnya perusahaan yang akan dipailitkan bila masih dapat dilakukan perbaikan terhadap perusahaan tersebut hendaknya dilakukan reorganisasi perusahaan. Ada berbagai kelemahan mendasar dari UU Kepailitan NO. 4 Tahun 1998, antara lain, tidak adanya batas utang yang jelas sehingga suatu perusahaan bisa dinyatakan pailit. Dimana menurut Undang-undang Kepailitan yang lama ini sangat sulit membuktikan atau mendefenisikan apakah itu utang atau tidak. Misalnya dalam kasus Manulife dengan
Bab I. Pendahuluan
6
Darmala beberapa waktu yang lalu.Tidak jelas apakah itu termasuk utang atau tidak. Demikian pula dalam kasus Prudential, masih menimbulkan kontroversi apakah pihak Prudential benar-benar punya utang dengan agennya yang memohon pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut.8 Putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tanpa melihat track record perusahaan yang akan dipailitkan, akan menjadi preseden buruk yang mempengaruhi investor, dari dalam negari maupun luar negeri, untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan hukum tidak memberi jaminan keamanan berusaha. Jadi dalam hal ini seolah-olah mudah untuk memohonkan pailit sehingga perusahaan yang sehat pun bisa dipailitkan. Hal ini adalah merupakan kelemahan UU Kepailitan (UU NO. 4 Tahun 1998) yang ditinjau dari sisi kepentingan masyarakat. Di dalam UU No. 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa bank dan pasar modal yang menghimpun dana publik hanya bisa diajukan pailit yaitu untuk bank oleh Bank Indonesia dan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tetapi justru asuransi yang juga salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat tidak mendapat hak yang sama seperti halnya bank dan pasar modal.9 Berdasarkan hal itulah sehingga direvisi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam UU No.37 Tahun 2004 dibuat ayat tambahan (Pasal 2 ayat 5) yang diusulkan oleh perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi serta dan pensiun dengan beberapa pertimbangan obyektif yakni:10 Pertama, harmonisasi dengan ketentuan perundangan yang berlaku disektor perbankan dan perusahaan sekuritas yang pengajuan permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh regulator yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Keempat sektor tersebut (perbankan, sekuritas, asuransi/reasuransi dan dana pensiun) adalah sesama jasa keuangan prudensial sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang setara. Regulator usaha asuransi/reasuransi dan dana pensiun adalah menteri keuangan.
8 Bismar Nasution, UU Kepailitan Harus Mengatur Reorganisasi Perusahaan,
Medan Bisnis, Sabtu 8 Mei 2004, hal. 8. 9 Bismar Nasution, loc. Cit. 10 Hotbonar Sinaga, Ketua Dewan Asuransi Indonesia, Oktober 2004, Judicial
Review UU Kepailitan. Majalah Ombusdman, hal. B8.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
7
Kedua, dari kasus-kasus permohonan dan keputusan pailit beberapa perusahaan asuransi (yang terbesar adalah pemailitan Manulife Financial tahun 2002 dan Prudential Life Assurance tahun 2004), perusahaan yang notabene Solvent ini dipailitkan walaupun akhirnya permintaan kasasi yang diajukan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Maka timbullah kepanikan di kalangan pemegang polis maupun pelaku di sektor asuransi dan investor asing termasuk pemerintahan negara lain yang mempersoalkan kasus aneh tetapi nyata ini. Ketiga, pemegang polis perusahaan asuransi yang dipailitkan (walaupun solvent), akan dirugikan karena mereka ‘dipaksa’ harus mengajukan klaim. Dalam istilah asuransi, pemegang polis harus menjual polisnya atau surrender dan bila hal ini terjadi akan menimbulkan rush karena seluruh pemegang polis tentunya akan meminta agar klaimnya segera dibayar. Untuk klaim yang mengandung unsur investasi, klaim nilai tunai yang dibayarkan perusahaan asuransi pada tahun awal pertanggungan, akan lebih kecil dibandingkan dengan akumulasi premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Sungguh tidak adil bila pemegang polis yang jumlahnya jauh lebih besar dipaksa untuk mengajukan klaim, yang berarti dirugikan, hanya untuk kepentingan segelintir “kreditor”. Keempat, dari penjelasan butir ketiga diatas, kepercayaan masyarakat khususnya pemegang polis terhadap perusahaan asuransi menjadi goyah. Akibatnya, peranan perusahaan asuransi sebagai salah satu mobilisator dana untuk pembangunan akan berkurang. Dari dua kasus yang disebutkan pada butir kedua diatas, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang dialamatkan kepada Dewan Asuransi Indonesia, mengapa perusahaan asuransi yang begitu besar (jumlah aset maupun pemegang polisnya) dan solvabilitasnya tergolong sangat sehat bisa dipailitkan. Memang ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1998 mengenai kepailitan tidak mempersoalkan apakah perusahaan yang dimintakan pailit itu sehat atau tidak keuangannya. Karena itulah masyarakat asuransi meminta agar dilakukannya koreksi. Kejanggalan yang menjadi pertanyaan masyarakat waktu itu, mengapa pula yang dipailitkan adalah (kebetulan?) perusahaan asuransi raksasa yang berpusat di luar negeri (Kanada dan Inggris) yang memiliki total kekayaan miliaran US Dollar. Apakah itu suatu kesengajaan atau merupakan kebetulan semata? Kelima, fungsi regulator dalam bisnis apapun juga adalah sebagai Pengawas maupun Pembina. Dalam usaha perasuransian, Departemen Keuangan adalah regulator yang paling mengetahui kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi (termasuk reasuransi dan dana pensiun). Pasal
Bab I. Pendahuluan
8
2 ayat (5) tersebut memungkinkan pihak regulator untuk memperantai serta menjadi juru damai antara kedua pihak (tertanggung dan penanggung) yang bersengketa. Dengan munculnya UU Kepailitan yang baru (UU No. 37 Tahun 2004) ini diharapkan secara sosiologis, bisa memulihkan dan menimbulkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada pemerintah; sedangkan secara yuridis, dapat memberikan kepastian dan kejelasan sebagai landasan hukum yang kuat. Dari contoh kasus diatas,seharusnya untuk menyelesaikan sengketa kepailitan dilakukan upaya reorganisasi perusahaan. Reorganisasi perusahaan dilakukan agar perusahaan mampu kembali membayar utangnya. Reorganisasi perusahaan dapat dilakukan melalui privatisasi, merger, akuisisi maupun penjadwalan utang. Artinya, suatu perusahaan tidak serta merta harus dipailitkan tanpa melihat prospeknya apakah masih layak dan bisa disehatkan atau tidak. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi mendefenisikan bahwa Reorganization adalah menstrukturkan kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan.11 Reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan:12 a. Reorganisasi yuridis, terjadi apabila ada perubahan bentuk
perusahaan. Misalnya perusahaan perseorangan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
b. Reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis.
c. Reorganisasi finansial, merupakan Capital Restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable.13 Tujuan reorganisasi finansial adalah untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk operasional perusahaan di masa yang akan datang.
11 Sutan Remi Sjahdemi, 2002, Hukum Kepailitan-Memahami
Faillissementsverordening juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 19.
12 Wasis, 1992, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni, Bandung, hal. 209-210 13 Bambang Riyanto dalam Munir Fuady, 1994, Hukum Bisnis dalam Teori dan
Praktek: Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
9
B. Perumusan Masalah
Mengacu kepada latar belakang tersebut, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Manfaat apa yang diperoleh dari dilakukannya reorganisasi
perusahaan? 2. Apakah telah cukup pengaturan reorganisasi perusahaan dalam
Undang- Undang Kepailitan? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, memang sudah ada yang meneliti atau membahas dalam bentuk tesis, makalah, majalah, artikel, bahan-bahan diskusi, seminar dan lokakarya, namun dengan permasalahan yang berbeda dan dari sudut pandang undang-undang yang berbeda pula. Khususnya setelah keluarnya Undang-undang Kepailitan yang baru, yakni UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena itu maka dapat dianggap penulisan buku (penelitian) ini memiliki keaslian. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui manfaat dari dilakukannya reorganisasi
perusahaan. 2. Untuk mengetahui pengaturan reorganisasi perusahaan dalam
Undang-undang Kepailitan. E. Manfaat Penelitian Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum kepailitan didalam pengaturan reorganisasi perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan tentang kepailitan mengenai pengaturan reorganisasi perusahaan di Indonesia.
Bab I. Pendahuluan
10
Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada investor dan masyarakat tentang pengaturan reorganisasi perusahaan didalam kepailitan. F. Kerangka Teori Secara umum prosedur kepailitan yang diatur dalam Faillisement Verordening tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya semakin kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional. Maka kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillisement Verordening melalui PERPU No.1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekwensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 NO. 135. Maka sejak tanggal Undang-undang tersebut disahkan berlakunya UU Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV. Namun pada tahun 2004 Undang-undang Kepailitan direvisi kembali. Pada tanggal 18 Oktober 2004 yang lalu disahkan Undang-undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang yakni UU No. 37 Tahun 2004 yang telah disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam UU No.37 Tahun 2004 juga masih terdapat kekurangan walaupun amademen Undang-undang Kepailitan cukup baik, terutama dari segi defenisi. Namun perbaikan undang-undang ini bersifat reaktif dalam menjawab persoalan yang lama. Dimana UU No. 37 Tahun 2004 belum memberikan solusi mengungkapkan kreditur fiktif. Hal ini
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
11
disebabkan pembuktian kreditur fiktif harus melalui proses pidana, yang memakan waktu cukup lama. Padahal, perkara kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hingga kini pengusutan dugaan kreditur fiktif ini tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Niaga.14 Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.15 Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dab harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.16 Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “Verordening op het Faillisement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 Faillisementverordening.17 Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.
14 http://hukumonline.com/detail.asp?id=11712&cl=Berita (“UU Kepailitan Belum
Memberikan Solusi Mengungkapkan Kreditur Fiktif”, 9 Desember 2004) 15 J. Djohansah, 2001, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, hal. 23. 16 http://www.solusihukum.com/artikel/artikel36.php (“Kepailitan di Indonesia,
Suatu Pengantar”, 19 Mei 2004) 17 Sutan Remi Sjahdemi, loc.cit, hal. ix.
Bab I. Pendahuluan
12
Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:18 Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proposional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditur (Pasal 1132) secara proposional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak Preferens).19 Dalam Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan seorang kreditur atau lebih. Dari ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa pada prakteknya ternyata cukup mudah untuk mempailitkan suatu perusahaan, karena syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Adanya debitur (misal suatu perusahaan) yang mempunyai dua atau
lebih kreditur (yang memiliki piutang), 2. Adanya permohonan dari perusahaan itu sendiri, atau 3. Adanya permohonan dari seorang kreditur atau lebih.
18 Sri Redjeki Hartono, 2000, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan
Modern”, Majalah Hukum Nasional No. 2 hal. 37. 19 Ibid.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
13
Disamping itu, proses pembuktian yang dipergunakan oleh pengadilan dalam permohonan kepailitan adalah proses pembuktian sederhana (sumir), yaitu apabila fakta atau keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dibuktikan oleh pemohon, maka permohonan pailit harus dikabulkan oleh hakim.20 Yang memprihatinkan, UU No. 4 Tahun 1998 tersebut ternyata tidak mengatur mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perbandingan antara aset perusahaan dengan kewajiban yang harus dilaksnakan. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kontroversi pada kasus dipailitkannya suatu perusahaan asuransi beberapa waktu yang lalu, yang ternyata perusahan tersebut memiliki RBC (Risk Based Capital) jauh diatas 100 persen. Yang dimaksud dengan RBC (Risk Based Capital) adalah suatu ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara aset dengan kewajiban. Pemerintah telah menetapkan bahwa suatu perusahaan asuransi diwajibkan memiliki RBC minimal sebesar 100 persen dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Maksudnya adalah, seandainya semua klaim pemegang polis jatuh tempo secara seketika, maka perusahaan tersebut sanggup untuk membayar seluruh kewajibannya kepada seluruh pemegang polis saat itu juga.21 Hal inilah yang menjadi dasar direvisinya UU No. 4 Thaun 1998, yang kemudian diganti dengan UU Kepailitan yang baru, yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk menghadapi tahun penentuan (1999) dan tahun kelahiran kembali perekonomian diperlukan tindakan koreksi. Begitu juga untuk memulihkan kembali kehidupan perusahaan yang sudah bergelimpangan kena dampak krisis moneter diperlukan koreksi dalam berbagai bentuk. Apalagi untuk menghadapi persaingan global tersebut tentu harus dilakukan suatu koreksi fundamental. Sementara pengusaha menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global tersebut. Mereka adalah proses bisnis, hubungan dengan pelanggan dan relasi bisnis, dan karyawan.
20 http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/14/teropong/konsul_hukum.htm
(Wirawan, SH, Sp.N/LBH Bandung) 21 Ibid.
Bab I. Pendahuluan
14
Dari berbagai massmedia diketahui bahwa pada tanggal 10 Januari 2000 terjadi pengumuman merger22 antar raksasa Internet, yaitu America Online (AOL) dengan Time Warner yang akan membentuk sebuah kelompok media dan Internet raksasa yang disebut AOL Time Warner Inc. Kombinasi perusahaan tersebut diperkirakan bernilai 350 miliar dolar AS dengan jumlah penjualan tahunan lebih dari 30 miliar dolar. Gabungan ini akan menjadi perusahaan global utama yang menyebarkan media layanan informasi, hiburan dan komunikasi. Ia akan mengendalikan perusahaan-perusahaan cabangnya seperti AOL, Time, CNN, Compuserve, Warner Bros, dan Netscape.23 Merger perusahaan tersebut diatas adalah merupakan salah satu contoh bentuk rektrukturisasi perusahaan, dalam kasus tersebut, tentunya untuk persiapan menghadapi persaingan global dalam rangka meningkatkan efesiensi dan daya saingnya. Pemulihan kembali perusahaan di Indonesia juga antara lain ditempuh dengan merger sebagai salah satu bentuk rekturisasi perusahaan. Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan lainnya adalah konsolidasi24, likuidasi, akuisisi, kepailitan (pembangkrutan), pemecahan usaha (split off), pemekaran usaha (spin off), penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), rekapitalisasi (penataan kembali permodalan), dan reorganisasi usaha. Sementara itu, untuk mengurangi ekuisitas negatif (negative equity) karena beban utang dilakukan beberapa tindakan misalnya penjadwalan kembali pelunasan hutang (rescheduling), pengurangan utang (hair cut), pembebasan utang (debt remission), konversi utang menjadi ekuitas (debt-equity swap), dan penyitaan barang-barang jaminan utang. Krisis moneter,
22 Istilah “Merger” ini sering disebut dengan “penggabungan” perusahaan. Yang
dimaksud dengan merger adalah suatu proses hukum untuk meleburnya (fusi) suatu perusahaan (biasanya perusahaan yang kurang penting) ke dalam perusahaan lain yang lebih penting, sehingga akibatnya perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar, dengan atau tanpa likuidasi. Lihat dalam Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 91.
23 Gunadi, Loc.cit. 24 Istilah “konsolidasi” sering juga disebut dengan “peleburan” perusahaan.
Istilah konsolidasi dimaksudkan adalah suatu proses hukum untuk meleburnya (fusi) 2 (dua) perusahaan atau lebih ke dalam perusahaan ketiga, yakni perusahaan lain yangn baru dibentuk, sehingga akibatnya kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar, dengan atau tanpa likuidasi, sementara yang tetap eksis tersebut adalah perusahaan ketiga yang baru dibentuk tersebut.
Yang dimaksud dengan “likuidasi” suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua tindakan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.
Istilah “akuisisi” dikenal juga dengan istilah “pengambilalihan”. Yang dimaksud dengan akuisisi adalah mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Lihat Gunadi, Ibid, hal. 93.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
15
menimbulkan kredit perbankan bermasalah (non performing) dan bahkan macet. Apabila pokok pinjamannya tidak dapat diperoleh kembali terlebih lagi bunganya. Dalam industri perbankan, pengakuan penghasilan atas bunga dimaksud nampak kurang realistis. Untuk menyelaraskan dengan kenyataan, terdapat perubahan saat pengakuan penghasilan bunga dari dasar waktu (akrual) menjadi dasar tunai (cash). Seperti diketahui bahwa di dalam menjalankan usaha, banyak peluang dan tantangan, kesempatan serta resiko yang dihadapi perusahaan. Perekonomian dengan pertumbuhan stabil berkesinambungan apalagi kalau dinamis dan booming banyak perusahan yang ekspansi dan melebarkan sayapnya untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang. Pembangkrutan usaha dapat dihindarkan, antara lain melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan,akuisisi usaha, dan bentuk lainnya. Reorganisasi tersebut juga dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usaha dan investasi (economic recovery), serta kesempatan kerja. Reorganisasi sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi. Pengertian restrukturisasi yang berhubungan dengan penyehatan perusahaan dapat dibagi dalam beberapa tahap pertama, bila seorang debitur mengalami kesulitan terhadap pembayaran utangnya, maka terhadap debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi hanya terhadap utang debitur, karena bila retrukturisasi terhadap debitur dianggap belum cukup menjamin penyehatan perusahaan, maka dapat dilanjutkan dengan restrukturisasi perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi perusahaan tersebut maka diharapkan restrukturisasi utang akan lebih terjamin keberhasilannya. Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan hanya restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang debitur dengan tujuan agar perusahaan debitur dapat sehat kembali.25 Restrukturisasi utang debitur hanya dapat dilakukan bila terjadi peristiwa sebagai berikut:26 (a) Perseroan sudah berada dalam keadaan tidak mampu membayar
bunga dab atau utang pokoknya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
25 Syamsudin Manan Sinaga, 2000, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Pembinaaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 7.
26 Syamsudin Manan Sinaga, loc. Cit.
Bab I. Pendahuluan
16
(b) Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mendatang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
(c) Perseroan berdasarkan putusan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang telah berkakuatan hukum tetap diwajibkan membayar utang atau ganti kerugian kepada pihak lain dan apabila perseroan memenuhi putusan pengadilan atau badan arbitrase tersebut, maka besarnya pembayaran kewajiban itu dapat mengakibatkan perseroan kehilangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
(d) Perseroan sudah mengalami kerugian yang besarnya kerugian itu mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
(f) Perseroan memiliki utang bermasalah yang besarnya setelah di perhitungkan dengan cadangan, masih akan mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
(g) Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 500% (lima ratus persen) dari modalnya.
(h) Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 200% (dua ratus persen) dibandingkan dengan nilai jual harta kekayaan perseroan seandainya perseroan dilikuidasi karena dinyatakan pailit.
Restrukturisasi terhadap utang debitur bukan hanya bila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga harus dipertimbangkan beberapa kelayakan berikut:27
(a) Perseroan masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang atau utang-utang tersebut apabila diberi kesempatan penundaan pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyratan dan atau diberi tambahan utang baru, dan
(b) Kreditur akan memperoleh pelunasan utang yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada perseroan dinyatakan pailit, dan atau
(c) Syarat-syarat utang berdasarkan restrukturisasi lebih menguntungkan bagi kreditur daripada sebelu dilakukan restrukturisasi.
Oleh karena itu sebelum restrukturisasi dilakukan, harus dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan yang bertujuan untuk menyimpulkan apakah utang debitur layak atau tidak layak untuk direktrukturisasi, baik
27 Ibid, hal. 9.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
17
retrukturisasi itu hanya terbatas pada retrukturisasi utang atau juga harus dilakukan retrukturisasi perusahaan. Studi kelayakan tersebut harus dilakukan oleh Kantor Konsultan Independen yang sekurang-kurangnya terdiri dari:28 1. Kantor Akuntan Publik. 2. Kantor Konsultan Hukum. 3. Kantor Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis. 4. Kantor Konsultan Penilai 5. Pakar mengenai sektor industri yang bersangkutan. Ketentuan restrukturisasi di Amerika Serikat, dimana bila seorang debitur sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, maka menurut Undang-undang Kepailitan di Amerika Serikat, ada beberapa pilihan: “The Bankruptcy Act covers several types of bankruptcy proceedings. In this chapter our fucos will be on (1) straight bankruptcy (liquidation), (2) reorganization, and (3) consumer debt adjusments”29 Chapter 11 Undang-undang Kepailitan di Amerika Serikat (Chapter 11 of the Bankruptcy Act) memberikan alternatif untuk memecahkan problema-problema finansial yang dihadapi oleh seorang debitur dengan menyusun sebuah rencana restrukturisasi. Debitur membuat rencana yang matang untuk terus melanjutkan bisnusnya serta melakukan negosiasi dengan para kreditur mengenai restrukturisasi finansialnya. Debitur yang merestrukturisasi bisnis berdasarkan chapter 11 akan mendapatkan keuntungan:30 1. Menghindarkan debitur dari kepailitan; 2. Memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan bisnisnya; 3. Para kreditur yang menolak rencana restrukturisasi bila rencana
tersebut telah mendapat persetujuan dari pengadilan federal, terpaksa menyetujuinya;
4. Bila rencana restrukturisasi tersebut berhasil, maka kreditur akan mendapatkan keuntungan dibandingkan jika debitur dipailitkan.
Ketentuan chapter 11 ini dapat digunakan oleh hampir semua bidang usaha (all bussiness enterprisers, including individual proprietorships, patnerships, and corporation) kecuali: 1. bank; 2. saving and loan associations;
28 Syamsudin Manan Sinaga, loc.cit. 29 Donnel, John D, 1983, Law For Business, Irwin Home Wood. Illinois, hal. 710. 30 Donnel, Jhon D, 1983, loc.cit.
Bab I. Pendahuluan
18
3. insurance companies; 4. commodities brokers; 5. stockbrokers. Permohonan untuk reorganisasi bisnis dapat dimohonkan oleh debitur (voluntarily) dan oleh kreditur (involuntarily). Ketika permohonan reorganisasi bisnisnya dikabulkan oleh pengadilan, maka oleh pengadilan ditetapkan pula: 1. a committee of creditors who hold unsecured claims; 2. a committe of equity security holder (shareholders); 3. a trustee.31 Trustee bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana reorganisasi bisnis debitur, juga bertanggungjawab atas tuntutan-tuntutan kreditur yang bermacam-macam, serta kepentingan banyak orang seperti pemegang saham untuk ditangani. Rencana reorganisasi pada hakekatnya adalah sebuah kesepakatan antara seorang debitur dan beberapa kreditur. Hal tersebut mungkin merupakan rekapitulasi perusahaan debitur dan atau memberi pada kreditur beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagian atau seluruh utang-utang perusahaan. Rencana reorganisasi harus meliputi: 1. Mengelompokkan kreditur ke dalam beberapa golongan; 2. Bagaimana membayar utang-utang kreditur; 3. Menentukan tuntutan-tuntutan yang akan dirugikan, bila rencana
dijalankan; 4. Memperlakukan sama semua kreditur yanng ada, kecuali kalau para
kreditur menyetujui bahwa ada di antara mereka yang diperlakukan berbeda.
Tujuan utama dari reorganisasi adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk bernafas. Oleh karena itulah begitu permohonan diajukan, kreditur dicegah untuk mengajukan gugatan. Agar debitur dapat melunasi utang-utangnya, menguasai kembali hak miliknya, dan mengeksekusinya. Hal ini dimaksudkan agar debitur dapat berusaha dengan tenang.
31 Syamsudin Manan Sinaga, op.cit, hal. 12.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
19
Dalam menjalankan suatu proses reorganisasi perusahaan, ada beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:32 (1) Adanya kebutuhan akan dana baru (new funds) yang akan
dipergunakan untuk modal kerja dan rehabilitasi properti. (2) Haruslah diketemukan dan minimalkan sebab-sebab kegagalan
operasi dan kegagalan managerial dari perusahaan yang direstrukturisasi.
(3) Adanya kegagalan dari perusahaan tersebut, baik karena ketidakmampuannya menunaikan kewajiban finansialnya pada`saat jatuh tempo ataupun karena jumlah kewajiban finansial melebihi aset-asetnya. Karena itu, haruslah dirombak sifat dan jumlah dari kewajiban finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam setiap tindakan reorganisasi suatu perusahaan, haruslah berkiblat kepada performance perusahaan yang lebih baik di masa depan setelah reorganisasi. Dengan perkataan lain, bahwa tindakan reorganisasi perusahaan haruslah feasible. Untuk itu, tindakan reorganisasi tersebut haruslah dapat meningkatkan earning power dari perusahaan yang bersangkutan. Earning power dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan tertentu dengan berbagai konsekuensi hukumnya masing-masing. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Restrukturisasi sumber daya manusia. (b) Restrukturisasi peralatan produksi atau peralatan kantor yang
sudah out of date. (c) Restrukturisasi hutang, seperti dengan melakukan
rescheduling, refinancing, haircut, converted debt dan lain-lain.
(d) Improvisasi beberapa sektor penting seperti improvisasi bidang produksi, pemasaran, iklan, dan lain-lain.
(e) Improvisasi atas produk yang dihasilkan atau bahkan memproduksi produk baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar.33
G. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
32 Ibid. 33 Fuady Munir, 1999, Hukum Tentang Merger, Cipta Aditya Bakti, Bandung, Hal.
6-7.
Bab I. Pendahuluan
20
kepustakaan.34 Penelitian hukum normatif didefenisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.35Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.36 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telahaan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:37 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telahaan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. Situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.
Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 23. 35 Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan
istilah penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process). Lihat Bismar Nasution,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.
36 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.
37 Ibid.
Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan
21
tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi. Dari data-data yang ada maka akan dianalisis secara induktif kualitatif agar dapat sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.