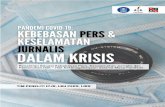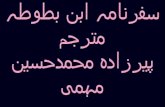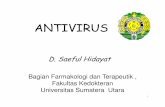(7) JURNAL@-Konstitusi & Persekusi Kebebasan Beragama di Daerah Arif Hidayat 2012
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of (7) JURNAL@-Konstitusi & Persekusi Kebebasan Beragama di Daerah Arif Hidayat 2012
PERLINDUNGAN KONSTITUSI DAN PERSEKUSI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DI INDONESIA
Oleh : Arif Hidayat
Pengajar HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Email: [email protected]
AbstractThis study investigated the constitutional protection of freedom of religion/belief in
Indonesia. Freedom of religion as a right that can not be subtracted under anycircumstances, have been guaranteed in Article 28 paragraph 1 of the 1945 Constitutionand some regulations about human rights in Indonesia. As one of the rights that can not bereduced, then the supposed religious rights are universal and non discriminatory. Legalreality of the product of discriminatory laws and regulations in their application has openeda space for the coating of the offense, whether "violence by judicial" or acts of persecutionthat is based on the reality of the laws that were discriminatory. Condition "silent majority"and vulnerable communities are also increasingly make room for the persecution ofreligious freedom. Decision of the Constitutional Court (MK) which have rejected theconstitutional review of the Act Number 1/PNPS/1965 about the Prevention of Abuse and/orthe desecration religious can be read as a reinforcement of the juridical existence relating tothe right of religious freedom. The decision constructing of the idea that various forms ofdesecration and blasphemy as violence in the name of religion or religious radicalism andthe persecution of freedom of religion/belief in Indonesia that is not caused by juridical theproduct in the era of the old order or juridical emergency product, but it is more caused bythe compilation of problems such as unfairness, disparity, and helplessness.
Keywords: Constitutional Protection, Right to Freedom of Religion/Belief
AbstrakPenelitian ini mengupas perlindungan konstitusi terhadap kebebasan
beragama/berkeyakinan di Indonesia. Hak beragama sebagai salah satu hak yang tidakdapat dikurang dalam keadaan apapun, telah dijamin dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945dan beberapa regulasi tentang hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai salah satu hakyang tidak dapat dikurangi, maka hak beragama semestinya berlaku secara universal dannon diskriminasi. Realitas legal diskriminatif produk peraturan perundangan-undangandalam aplikasinya telah membuka ruang bagi terjadinya pelapisan pelanggaran, baik“violence by judicial” maupun tindakan persekusi yang didasarkan pada realitas produkhukum yang diskriminatif. Kondisi “silent majority” dan masyarakat yang rentan jugasemakin memberikan ruang bagi persekusi kebebasan beragama. Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang telah menolak Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,dapat dibaca sebagai penguatan terhadap eksistensi yuridis yang berhubungan denganhak kebebasan beragama. Putusan tersebut mengkonstruksi pemikiran bahwa berbagaibentuk penodaan dan pelecehan agama seperti kekerasan atas nama agama atauradikalisme agama maupun persekusi kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi diIndonesia bukanlah disebabkan oleh produk yuridis di era orde lama atau produknyabersifat darurat, tetapi lebih disebabkan oleh kompilasi permasalahan sepertiketidakadilan, disparitas, dan ketidakberdayaan.
Kata Kunci: Perlindungan Konstitusional, Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
A. Pendahuluan
UU No.1/PNPS/Th.1965 maupun pemberlakuan turunan dalam
putusan politik baik berupa SKB (Surat Keputusan Bersama)
Tiga Menteri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008
tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat, maupun Perber (Peraturan Bersama)
Menag dan Mendagri 2006 yang merupakan revisi dari Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri No. 1/1969, dalam
praktiknya justru terbukti menjadi acuan bagi suatu kelompok
untuk meniadakan -bahkan dengan kekerasan- kelompok lain,
atas dasar klaim ”penodaan agama”.1
Selain itu, terdapat sekitar 21 produk kebijakan yang
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintaan,
baik di tingkat nasional maupun lokal mengenai ”Peringatan
dan Perintah terhadap Kelompok Ahmadiyah”, yang mencantumkan
UU No. 1/1965 sebagai dasar hukumnya.2
Persoalan utama di balik regulasi tersebut dikarenakan
negara mendominasi ranah privat agama. Hak kebebasan
1 Kasus penyerangan dan penyerbuan terhadap kelompok Ahmadiyah yangterus menerus terjadi sampai saat ini
2 ____________, Laporan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2010, hlm. 6.
beragama yang semestinya hanya ada pada Tuhan dan penganut
agama, telah diambil oper oleh negara. Dengan demikian,
wewenang negara pada agama sudah jauh menyimpang, bukan lagi
pada tataran yang semestinya, “tataran batasan agama” (at the
boundaries of religion), tapi sudah “melintasi tataran batasan
agama” (across the boundaries of religion) dengan mencampuri urusan
intern agama. Akibatnya, kelompok agama minoritas mengalami
upaya pengerdilan agama (the trivialization of religion).3
Kebebasan berkeyakinan dan larangan penodaan agama
adalah dua entitas yang selalu mengalami pergulatan serius
terkait HAM (Hak Kebebasan Berkeyakinan). Kenyataan seperti
inilah yang sedang dialami UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bila
dilihat dari satu sisi, para pemohon judicial review, UU ini
telah merenggut kebebasan berkeyakinan. Alasannya, selama
ini telah banyak terjadi justifikasi penyesatan terhadap
kelompok minoritas keberagamaan. Mereka yang mempunyai
penafsiran lain terhadap ajaran agama dianggapnya sesat dan
telah menodai atau melecehkan suatu ajaran agama.
Bila dilihat dari sisi pendukung UU ini, larangan
penodaan agama merupakan instrumen untuk menjaga kebebasan
berkeyakinan tersebut agar selalu memperhatikan kerukunan
berkeyakinan. Dalam pandangan mereka, kebebasan menjalankan
ibadah harus selalu dikontrol. Salah satu kontrolnya adalah
menegaskan bahwa kebebasan berkeyakinan sebenarnya merupakan
kebebasan bersyarat. Dengan persyaratan ini, seseorang tidak
boleh mengekspresikan keberagamaannya dengan cara melukai
3 Benyamin F. Intan, “Peraturan Bersama (Perber) Kontraproduktif”, OpiniHarian Seputar Indonesia (Sindo), Selasa, 21 September 2010.
atau menodai ajaran suatu agama. Oleh sebab itulah
diperlukan peran negara membuat peraturan yang mengontrol
kebebasan berkeyakinan agar tidak terjadi penodaan agama.
Perdebatan demikian telah terjadi dalam sidang constitutional
review UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi
menolak permohonan constitutional review.
Penulis perlu memberikan beberapa koridor penulisan
hasil penelitian ini agar tidak mengalami perluasan
pembahasan yang tidak fokus dan menghindari kesimpangsiuran
penyajian. Pertama, kebebasan agama/berkeyakinan akan
dianalisis dengan perspektif Hukum & HAM dan relasi negara-
agama dalam perspektif kewenangan negara mengawal pemenuhan
HAM bidang kebebasan beragama/berkeyakinan. Kedua, penulis
juga perlu mempertegas bahwa bahasan kajian ini berkaitan
dengan persekusi kebebasan beragama/berkeyakinan di beberapa
daerah melalui pemantauan mediatik. Ketiga, mengenai masalah
undang-undang, penulis hanya akan membahas UU
No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama dan putusan judicial review-nya, serta hanya dalam
aspek materiilnya.
B. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah
pendekatan dengan melakukan penelitian secara mendalam
terhadap hukum yang berlaku. Penelitian normatif yang
berpangkal pada pendekatan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dengan menganalisis keterhubungannya dengan
persoalan kebebasan beragama. Pengkajian ini dapat
digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan
pendekatan konseptual (conseptual approach). Melalui pendekatan
konseptual, peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum
yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
atau doktrin-doktrin hukum. Metode analisis yang digunakan
adalah metode analisis krisis (critical analysis) melalui
pendekatan analisis komprehensif (comprehensive analysis).
Pengolah dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif
berdasarkan sajian (penyajian hasil penelitian) deskriptif.4
Tipe penelitian bersifat eksploratif5 yaitu suatu
penelitian yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan
mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-
ide baru mengenai suatu gejala tertentu tersebut. Pemantauan
mediatik di beberapa daerah sebagai lokus area penelitian
dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan, agar mampu
menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji
sebagai ius constituendum.6
C. Pembahasan
1. Pola Relasi Agama-Negara
Dalam rangka “pelibatan diri” negara untuk
memelihara kerukunan beragama/berkeyakinan, para founding
fathers telah membangun negara yang berdasarkan Pancasila.4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, (Jakarta: UI-
Press, 1986), hlm. 6. 5 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Kelima, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2003), hlm. 25. 6 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,
Ifdhal Kasim (Ed.). (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002) hlm. 146-170.
Konsep ini berarti bahwa negara bukan berdasarkan satu
agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara tidak
identik dengan agama tertentu karena negara melindungi
semua agama yang ingin dipeluk rakyatnya asalkan tidak
menyimpang. Negara juga tidak melepaskan agama dari
urusan negara. Negara bertanggungjawab atas eksistensi
agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama.
Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat
dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau
kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang
bertalian dengan kehidupan keagamaan.7
Hal ini kemudian ditegaskan juga dalam Pembukaan UUD
1945 Aline IV bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut
maka Pancasila sebagai sebuah sistem ideologi adalah
menjadi dasarnya. Pancasila mempunyai 5 (lima) Sila yang
di antara mereka adalah merupakan satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Ketika
memaknai arti Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa maka
akan hadir juga aspek kemanusiaan yang mempunyai segi
universalitas (human being as a whole), persatuan nasional
yang menjaga pluralitas, demokrasi yang agung (wisdom) dan
takzim terhadap kehendak rakyat, serta kesejahteraan
untuk semua yang searah dengan rasa keadilan.
Putusan a quo secara spesifik dan legal text adalah
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, namun dalam kerangka di mana hukum itu akan eksis
7 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945 (Jakarta: UniversitasIndonesia Press, 1995), hlm. 146.
dan berkorelasi sosial-antropologis maka akan sangat
terkait erat dengan aspek ber-Ketuhanan dalam ranah
publisitas berkeagamaan dan berkeyakinan di Indonesia.
Kedudukan Undang-Undang tersebut kemudian secara
sederhana dan awam akan mudah dikaitkan, legitimasi
maupun eksistensinya, dengan Sila Ke-1 Pancasila yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tentu sangat logis,
akan tetapi akan begitu bermasalah ketika Sila Ke-1
tersebut tidak dikaitkan dengan sila Pancasila yang
lainnya sebagai satu kesatuan. Lebih luas lagi,
menyangkut Pancasila sebagai ideologi yang terbuka,
Indonesia telah menjadi bagian dari sistem hukum
internasional yang dalam beberapa dekade ini telah dengan
masifnya mengintrodusir norma-norma hak asasi manusia
(HAM) yang bahkan telah diadopsi menjadi hak-hak
konstitusional melalui amandemen ke-2 UUD 1945.
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi,
diantaranya, 2 (dua) kovenan penting HAM Internasional
yaitu Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prinsip
pokok dari hak asasi manusia adalah ketidakterpisahan
(indivisibility) antara hak-hak yang satu dengan yang lainnya.
Memenuhi hak kebebasan beragama suatu kelompok tidak
berarti boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok
beragama atau berkepercayaan lainnya. Prinsip kesetaraan
(equality) harus selalu mengikuti setiap tindakan pemenuhan
kewajiban ne gara dalam penegakan hak asasi manusia
(protect, promote, fulfil).8
Dalam konteks kesetaraan terhadap semua pemeluk
agama dan kepercayaan, aspek perlindungan terhadap
kelompok minoritas yang rentan (minority-and-vulnarable groups)
harus mendapatkan perhatian yang lebih karena sejarah
telah membuktikan adanya kekerasan-kekerasan yang mereka
dapatkan baik oleh kelompok beragama lainnya (comission)
maupun minimnya perlindungan oleh negara (omission).9
Dengan melihat konstelasi hukum, hak asasi manusia,
Pancasila, dan pluralitas bangsa maka sudah sewajarnya
jika pertimbangan hukum dalam proses constitutional review UU a
quo oleh semua pihak (pemohon, pihak terkait, dan
terutama Mahkamah Konstitusi) sepatutnya, dan boleh
dikata tidak ada pilihan lain kecuali harus menggunakan
pendekatan yang komprehensif, interdisipliner, dan
kembali kepada kaidah-kaidah penafsiran hukum yang
menjunjung tinggi semangat keadilan dan kesetaraan
sebagai muara akhir dari alasan mengapa hukum itu
diciptakan.
Pendekatan para pemohon constitutional review UU
1/PNPS/1965 yang mengikuti pikiran sekularisme telah
menjebak bukan hanya ke dalam pemikiran yang rancu, juga
secara sadar atau tidak, ke dalam pikiran yang cenderung
berbeda dengan Pancasila. Sila pertama yang berbunyi
“Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi dasar yang memimpin8 Vide: Pasal 2 Par.1 ICCPR, Pasal 2 Par.2 ICESCR, Pasal 28I (2) UUD
1945, Pasal 3 (3) UU No.39/1999 tentang HAM.9 Hak atas affirmative action berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU No.39/1999
tentang HAM.
sila-sila yang lain, sebagaimana yang ditafsirkan oleh
Bung Hatta. Penafsiran Bung Hatta ini, apabila ditilik
dari sudut Islam, maka sila Ketuhanan yang Maha Esa tiada
lain identik dengan prinsip tauhid yang berhubungan
secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan,
persamaan, kekebasan, persaudaraan dan musyawah.10
Gagasan ini sekaligus sangat berbeda dengan
sekularisasi Nurcholis. Dia pernah menyatakan negara
merupakan salah satu segi kehidupan duniawi yang
dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama
merupakan aspek kehidupan lain (ukhrawi) yang dimensinya
adalah spiritual pribadi. Gagasan ini sekaligus langsung
mendapat kritik dari Prof. Rasjidi. Salah satu kritik
yang tajamnya seperti “agama Islam tidak hanya berdimensi
spiritual dan personal saja, tetapi sekaligus juga
berdimensi duniawi, sosio-kolektif”. Hal ini seperti iman
yang menjadi motor penggerak untuk melakukan karya
sosial.11 Dengan demikian pada dasarnya, antara agama dan
negara memang secara fitrah tidak bisa saling memisahkan
diri.
Dalam kasus eksistensi UU 1/PNPS/1965, hukum hendak
dirumuskan manusia tidak hanya hanya berangkat dari satu
segi penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-
10 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturandalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 152-157.
11 Buku yang dapat dibaca mengenai pemikiran Nurcholis Madjid, Islam,Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1989) dan Nurcholis Madjid, Islam,Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992). Sedangkan bukupengkritik dari pemikiran Nurcholis adalah Rasjidi, Koreksi terhadap Drs NurcholisMadjid tentang Sekularisasi (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) dan Faisal Ismail,Sekularisasi: Membongkar Kerancauan Pemikiran Nurcholis Madjid (Yogyakarta: YayasanNawesea, 2008).
mata hanya bertakluk kepada unsur-unsur yang ada dalam
pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakatnya
itu. Memang keberadaan perhubungan antar manusia dengan
manusia merupakan hak asasi antar sesama manusia. Namun
melebihi semua itu, setiap manusia yang menjadi anggota
masyarakat itu mempunyai pula –mau tidak mau– kewajiban
menciptakan hukum yang berguna untuk sesuatu yang
berhubungan dengan Tuhannya yang Maha Esa.12
Berkenaan dengan inilah Hazairin memperjelas
hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara hanya
bertugas menjamin kerukunan umat beragama melaksanakan
peribadatannya. Sedangkan mengenai keabsahan peribadatan
suatu agama diserahkan kepada masing-masing institusi
agama yang mempunyai kewenangan untuk hal itu. Hazairin
menafsirkan rumusan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
antara lain sebagai berikut: “Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yangbertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang dianut umatberagama di Indonesia. Negara RI wajib menjalankan syariat bagimasing-masing agama sesuai dengan syariatnya. Syariat yang tidakmemerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dankarena itu dapat berdiri sendiri adijalankan oleh setiap pemelukagama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allahbagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri-sendiri.”13
Pada tahun 1967, pemerintah telah mengambil
inisiatif untuk melakukan Musyawarah Antar-Umat Beragama
yang diharapkan dapat melahirkan gentlemen agreement di
antara para tokoh dan pemimpin agama dalam memelihara
kerukunan. Sayangnya, gentlemen agreement tersebut ditolak
oleh peserta dari agama Katolik dan Protestan karena12 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 72.13 Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm. 18-19.
terdapat klausul tentang larangan menyebarkan agama
kepada mereka yang telah memeluk suatu agama. Padahal di
sisi lain, peserta dari Islam, Hindu dan Budha menyambut
baik pengaturan itu dan sudah menyetujuinya.14
Tidak surut keinginan menciptakan kerukunan hidup
beragama, tahun 1969, terdapat tindak lanjut pertemuan
sebelumnya dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-
MAG/1969 tentang “Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembanan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya”.
Selanjutnya, lahir beberapa Surat Keputusan lagi untuk
lebih mendukung regulasi sebelumnya. Sebagai tindak
lanjut regulasi jaminan akan ketertiban ibadah masing-
masing pemeluk agama, pemerintah membuat aturan
menyangkut tatacara penyebarluasan ajaran agama khusus
kepada pemeluknya dan penerimaan bantuan suatu lembaga
keagamaan dari luar negeri. Regulasi ini sebagaimana
tercermin dalam satu tahun saja, yakni 1978. Pada tahun
ini lahir dua Surat Keputusan sekaligus, yakni SK Menteri
Agama No. 70/1978 tentang “Pedoman Penyiaran Agama” dan
SK Menteri Agama No. 77/1978 tentang “Bantuan Luar Negeri
Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia”.
Berikutnya, kita dapat membaca posisi UU
No.1/PNPS/Th.1965 bukannya sebagai justifikasi wewenang
negara untuk menghakimi suatu penganut aliran yang14 M. Natsir, Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama di Indonesia (Jakarta:
Media Dakwah, 1992). AM. Fatwa “ HAM, Pluralsime Agama dan KetahananNasional” Anshari Thayib (ed), HAM dan Pluralisme Agama (Surabaya: Pusat KajianStrategi dan Kebudayaan, 1997), hlm. 35.
dianggap sesat. Justifikasi sesat sepenuhnya masih
diserahkan kepada pihak yang berwenang. Untuk itulah
sebenarnya Pasal 2 mempunyai sinkronitasnya di sini.
Pasal itu dalam ayat 1 mengatakan “Barang siapa melanggar
ketentuan tersebut dalam Pasal 1 (penodaan agama) akan diberi perintah
dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu
keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri”. Baru kemudian dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan
pembubaran bagi aliran tersebut berada di tangan
Presiden.
Ketiga komponen itu –agama, hukum dan negara–
apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris
yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara
satu dengan lainnya. Agama sebagai komponen pertama
berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia
merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh
hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Negara sebagai
komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Posisi
tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris
ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu
agama dan hukum.15
Berangkat dari ketiga komponen di atas, UU ini
berguna menjamin kerukunan beragama agar tidak dirusak
oleh kebebasan beragama berkeyakinan. Berikut adalah
argumen hukum Mahkamah Konstitusi: “Bahwa negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasidan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan.
15 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Studi-studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihatdari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 43.
Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaankebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragamaorang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untukmencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible)”. “…bahwadari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepadasetiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dankebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengantanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang”. 16
Dalam sebuah ungkapan, sebagaimana dikutip Munawir
Syadzali, bahwa “Freedom is not licensee”. Seperti yang tertera
dalam Pasal 1 dari Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerances and of Discrimination based on Religion and Belief (1981),
pemerintah dapat mengambil langkah melalui perundang-
undangan untuk mengatur agar kebebasan
beragama/berkeyakinan, serta kebebasan mengamalkan ajaran
agama dan berdakwah, jangan sampai menganggu keserasian
dan kerukunan hidup beragama yang pada gilirannya akan
membahayakan stabilitas politik dan kesinambungan
pembangunan.17 Dengan demikian, jaminan yang diberikan
kepada negara adalah kebebasan yang bersyarat. Kebebasan
bukan berarti seseorang bebas sama sekali untuk berbuat
semau dia.
2. Kebebasan Beragama dari Sudut HAM
Kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia
berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang
meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak
individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (non
derogable rights). Karena itu, definisi-definisi yang
digunakan mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin16 Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 295. 17 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 230.
hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama merupakan hak
asasi manusia fundamental, melekat (in heren) pada diri
manusia karena eksistensinya sebagai manusia, sehingga
HAM harus dihormati karena diberikan oleh Tuhan bukan
diberikan oleh negara. Secara naturalis, HAM
didefinisikan sebagai hak-hak kodrati yang dimiliki
seluruh manusia di setiap saat dan di setiap tempat
semenjak lahir menjadi manusia.18 Hak-hak tersebut
meliputi hak hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan
seperti dinyatakan oleh Locke. Meminta pengakuan terhadap
hak-hak ini, sebagai contoh pengakuannya perlu mendapat
legitimasi dari negara, maka akan mereduksi hak-hak asasi
menjadi hak-hak hukum.19
Ahli HAM di Indonesia, seperti Muladi20 dan
Seotandyo21, juga mempunyai pendapat yang sesuai dengan
aliran naturalis di atas. Menurut mereka, HAM adalah hak
yang melekat (in heren) dalam diri setiap manusia karena
posisinya sebagai manusia. Pengertian ini kemudian telah
diakomodasi dalam Pasal 1 UU 39/1999 menyatakan bahwa HAM
adalah separangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,
18 Jack Donelly, The Concept of Human Rights (New York: St Martin’s Press,1985), hlm. 8-27.
19 Maurice Cranston, What Are Human Rights? (New York: Basic Books, 1962),hlm. 1-3.
20 Muladi, Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia (Jakarta: The HabibieCentre, 2002).
21 Soetandyo, HAM: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik Pada Masa AwalPerkembangannya, dalam Kumpulan Tulisan tentang HAM (Surabaya: PUSHAM UNAIR,2003).
Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.22
Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif
hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan
tertutup tapi dikonstruksikan secara luas.
Kesalahapahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan
kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut
agama. Perspektif hak asasi manusiajuga menegaskan, baik
penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak
mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak
dan harus mendapat perlindungan.23
Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan
internasonal ini melalui UU No. 12/2005 tentang
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum
(legaly binding) dan sebagai negara pihak (state parties) yang
telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya
sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan
memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.
Berdasarkan instrumen hak asasi manusia dan
Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional
kebebasan beragama/berkeyakinan kebebasan meliputi
kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan
pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama
atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi,
mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup,
22 UU 39/1999 tentang Ketentuan Pokok HAM.23 Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993
termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan
untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.24
Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata
internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak
(state parties); artinya negara adalah subyek hukum yang
berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Indonesia
sebagai subyek hukum dalam hukum internasional hak asasi
manusia berkewajiban (obligation of the state) untuk menghormati
(to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan setiap orang
atas agama atau keyakinan.
Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan
ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia,
namun berdasarkan prinsip siracusa25 yang telah
disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi
HAM, yaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak yang tak
dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan derogable
rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan
pemenuhannya).26
Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni forum
internum (kebebasan internal) di mana tak ada satu pihak
pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi)24 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang
berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal initermasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untukmenyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya,mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
25 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan danderogasi hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasimanusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italiatahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasiatas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.
26 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD NegaraRI 1945
terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan
kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan
internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan
berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut
atau tidak menganut suatu agama.27 Sedangkan kebebasan
sosial atau forum externum (kebebasan eksternal), dalam
situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi
atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan
margin of discretion atau prasyarat yang ketat dan legitimate
berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa. Termasuk dalam
rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk
beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik
secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk
mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan
simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari
besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin
agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran
agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada
anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola
organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk
menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi
keagamaan.28
Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan
(violation of right to freedom of religion or belief) adalah tindakan
penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak27 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981
tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi BerdasarkanAgama/Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.
28 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, KomentarUmum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentangPenghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.
dan kebebasan dasar seseorang untuk
beragama/berkeyakinan, yang dilakukan oleh institusi
negara, baik berupa tindakan aktif (by commission) maupun
tindakan pembiaran (by comission). Intoleransi merupakan
turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem
kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang
lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari
kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain
hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti
Apartheid atau penghancuran orang secara disengaja
melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal
dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.29
Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”30
Mengacu pada pemaparan definisi-definisi di atas,
maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran,
yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang
memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur
29 UNESCO, Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education forPeace, Human Rights and Democracy (Preliminary version), (Paris: UNESCO, 1994), hlm. 16
30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan
seseorang dalam beragama/berkeyakinan (by commission); dan
[b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi
terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (by
omission).
3. Persekusi Kebebasan Beragama di Indonesia
UU No.1/PNPS/1965 memberi kewenangan penuh kepada
negara untuk: (1) melalui Depag menentukan “pokok-pokok
ajaran agama”; (2) menentukan mana penafsiran agama yang
dianggap “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama” dan
mana yang tidak; (3) jika diperlukan, melakukan
penyelidikan terhadap aliran-aliran yang diduga melakukan
penyimpangan, dan menindak mereka. Dua kewenangan
terakhir dilaksanakan oleh BAKORPAKEM,31 yang semula
didirikan di Depag pada tahun 1954 untuk mengawasi agama-
agama baru, kelompok kebatinan dan kegiatan mereka.
Namun, semenjak 1960 tugas dan kewenangan diletakkan di
bawah Kejaksaan Agung. Sampai dengan tahun 1999,
Kejaksaan di berbagai daerah telah mengeluarkan 37
keputusan tentang aliran kepercayaan/keagamaan, dan
31 Keputusan Jaksa Agung RI no. KEP 108/J.A./1984 tentang pembentukantim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Keputusan JaksaAgung ini merupakan landasan dari berdirinya Team koordinasi PAKEM (TeamKoordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk daritingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten. Team Pakem di tingkat Pusatterdiri dari unsur Depdagri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kejaksaan Agung, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, MABES ABRI, BAKINdan Mabes Polri.
kepolisian menyatakan 39 aliran kepercayaan dinyatakan
sesat.32
Masalah agama bukanlah menjadi urusan pemerintah
daerah dalam konteks otonomi daerah. Hanya saja, berbagai
kebijakan restriktif dan diskriminatif di tingkat
nasional tetap efektif dijalankan oleh para penyelenggara
pemerintahan daerah dan menjadi pemasung kebebasan
beragama/berkeyakinan. Politisasi agama terjadi dan
menguat di daerah-daerah dalam berbagai ritual politik
Pemilihan Kepala Daerah. Di beberapa daerah yang
mayoritas berpenduduk Islam, politisasi agama masih cukup
dominan menjadi kapital politik di daerah. Agama dan
etnisitas lainnya, di beberapa daerah, masih menjadi
kapital politik yang efektif mendulang dukungan publik.
SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008, No.
KEP-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah
Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,
sama sekali tidak menghentikan persekusi terhadap
kelompok Ahmadiyah. Jikapun kekerasan terhadap Ahmadiyah
berkurang, hal itu bukanlah dampak SKB yang dianggap oleh
pemerintah sebagai penyelesaian. Sejumlah kekerasan dan
pembakaran masjid Ahmadiyah tetap masih terjadi. Beberapa
pemerintah daerah aktif merujuk SKB ini sebagai landasan
‘penertiban’ jemaat Ahmadiyah.33 32 Uli Parulian Sihombing dkk, “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap
Pengawasan Agama dan Kepercayaan”, (Jakarta: ILRC, 2008), hlm. 109-11733 Di NTB, dengan dalih telah terbit SKB, pembiaran terhadap pengungsi
internal jemaat Ahmadiyah terus berlangsung. Bantuan makanan juga telahdihentikan. Di Parakansalak Sukabumi, pemerintah setempat juga aktifmelakukan sejumlah tindakan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk
SETARA Institute, menyebutkan bahwa ada 10 wilayah
dengan tingkat persekusi kebebasan beragama/berkeyakinan
tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38
peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10
peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera
Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8
peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa
Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa). Kecuali Bali
dan NTT, 8 daerah lainnya merupakan daerah yang pada
tahun-tahun sebelumnya juga membukukan peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama cukup tinggi. Jawa Barat
dan Jakarta bahkan selalu menempati urutan tertinggi.
Dari 200 peristiwa pelanggaran yang terjadi, di dalamnya
tercatat 291 tindakan pelanggaran. Perbedaan jumlah
tindakan pelanggaran dengan peristiwa yang terjadi,
muncul karena dalam satu peristiwa dapat terjadi berbagai
bentuk tindakan, misalnya, di dalam satu peristiwa
pengrusakan tempat ibadah, terdapat juga tindakan
penganiayaan terhadap jemaat, perampasan properti, dan
lain-lain. 34
Dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia,
kerangka hukum pidana, dan kerangka etik demokrasi,
SETARA Institute membagi tindakan sejumlah 291 tindakan
tersebut sebagai berikut.35
pencabutan izin sekolah, penghentian hibah bagi madrasah, dan masjidnyadibakar. Di Kuningan, kondisi Ahmadiyah sedikit lebih baik dibanding tahunsebelumnya. Enam masjid yang sempat ditutup saat ini telah dibuka kembali.Meski demikian, pengucilan oleh masyarakat tetap terjadi. Lihat Harian UmumRepublika, 5 Juli 2009.
34 Margiyono, dkk., Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi KebebasanBeragama/Berkeyakinan di Indonesia, (Jakarta: Setara Institute, 2010), hlm. 22.
35 Ibid., hlm. 27.
Tabel 1Rincian Kategori Tindakan Persekusi Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan
No Kategori Jumlah1 Sejumlah 139 tindakan negara terdiri dari:
a. tindakan aktif negara (by commission) 101 tindakanb. tindakan pembiaran oleh negara (by
omission)38 tindakan
pembiaran atas terjadinya kekerasan yangdilakukan warga negara
23 tindakan
tindakan tidak memproses secara hukum 15 tindakan2 Sejumlah 152 tindakan warga negara terdiri dari :
a. tindakan kriminal/perbuatan melawan hukum
86 tindakan
b. tindakan intoleransi 66 tindakan
Terhadap pelanggaran kategori by commission dan by
ommission kerangka legal untuk mempersoalkannya adalah
kerangka hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia
yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang
terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi
manusia. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang
dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka
legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).
Tindakan intoleransi dalam berbagai bentuknya
sebenarnya bisa dipersoalkan dengan menggunakan Pasal 156
KUHP, hanya saja selama ini aparat penegak hukum tidak
pernah menerapkannya untuk menjerat praktik-praktik
intoleransi. Yang terjadi justru aparat hukum menerapkan
pasal 156a untuk menjerat orang-orang yang dituduh
melakukan penodaan agama. Dengan demikian, kategori
tindakan intoleransi tidak pernah diperkarakan dan
diadili.
Kategori pelanggaran by commission dan by ommission
dalam kerangka hukum hak asasi manusia merupakan bentuk
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, karena negara
merupakan state parties yang terikat baik secara hukum (legally
binding) maupun terikat secara moral (morally binding) karena
telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil
dan Politik (ICCPR).
Pada kategori tindakan aktif negara, SETARA
Institute36 mencatat 101 tindakan pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan. Berikut ini adalah tabel yang
menunjukkan bentuk-bentuk tindakan negara dan beberapa
narasi peristiwa.Tabel 2
Rincian Kategori Tindakan Negara
Tindakan Aktif Negara (By Commission) JumlahDesakan pelarangan keyakinan 1Diskriminasi akses atas hak memperoleh pendidikan 1
Diskriminasi akses hak atas pekerjaan 1Diskriminasi akses hak atas hidup yang layak 1Diskriminasi hak atas pelayanan sipil 1Dukungan penyesatan keyakinan/aliran keagamaan 4Pelaporan atas keyakinan/aliran keagamaan 1Pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan 8Pelarangan keyakinan/aliran keagamaan 17Pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan 1
36 Ibid., hlm. 32.
Pelarangan mendirikan rumah ibadah 3Pemaksaan pindah keyakinan 4Pembongkaran tempat ibadah 2Pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan 2Pemeriksaan Kepolisian & di Pengadilan 2Penahanan 7Penangkapan atas tuduhan sesat 8Penetapan status tersangka penodaan agama 2Pengabaian hak bagi IDPs 1Pengintaian aktivitas keagamaan 5Pengusiran Mahasiswa SETIA 2Pengusiran warga yang dituduh sesat 1Penuntutan 4Penyeragaman perilaku keagamaan 3Penyesatan keyakinan/aliran keagamaan 11Penyidikan tuduhan penodaan agama 3Tuduhan penodaan agama/keyakinan 2Vonis Pengadilan 3
Jumlah Tindakan Aktif Negara 101Pembiaran (By Omission) Jumlah
Pembiaran atas aksi kekerasan 23Pembiaran tidak memproses secara hukum 15
Jumlah Tindakan Pembiaran 38TOTAL TINDAKAN NEGARA 139
Bahkan dalam proses perkara constitutional review UU
1/PNPS/1965 sekalipun, terjadi beberapa persekusi yang
mengarah pada stigmatisasi Atheis.37 Teror dan intimidasi
menwarnai proses persidangan dan dialamatkan kepada
pemohon, kuasa pemohon, saksi dan ahli yang mendukung
pencabutan UU Penodaan Agama. Pada tanggal 12 Maret 2010,
37 Lihat, beberapa artikel online: “Hasyim: Waspadai Gerilya Kelompok Ateis.”Selasa, 16 Pebruari 2010,http://www.antaranews.com/berita/1266296609/hasyim-waspadai-gerilya-kelompok-ateis diakses terakhir 15 Oktober 2010; “Majelis Ulama Nilai Uji MateriUndang-Undang Penodaan Agama Keliru” Senin, 01 Februari 2010http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.html, diakses terakhir 15 Oktober 2010;http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/menag-minta-nu-dukung-uupenodaan-agama-17154; “Ketua Komnas Perempuan Diteriaki PKI” Jum’at, 12 Maret2010, http://news.okezone.com/read/2010/03/12/339/312013/ketua-komnas-perempuan-diteriaki-pki, diakses terakhir 15 Oktober 2010.
Ulil Abshar Abdalla, mendapatkan ancaman kekerasan dengan
teriakan ”halal darahnya” dan acaman “bunuh” di dalam
ruang persidangan.38 Teror dan intimidasi terjadi pula ke
kantor LBH Jakarta.39 Kekerasan terhadap Ahli, Saksi, dan
Kuasa Pemohon puncaknya terjadi pada sidang terakhir
yaitu persidangan tanggal 24 Maret 2010.40
4. Putusan MK & Kebebasan Beragama
Salah satu argumen MK dalam merumuskan keputusan
dalam constitutional review ini adalah, UU No.1/PNPS/1965 tidak
ada hubungan dengan kebebasan beragama, tapi hanya
terkait dengan penodaan agama. Berikut ini penulis akan
mengutip sejumlah pernyataan yang menjadi pertimbangannya
MK dalam mengambil keputusan. Sejumlah pernyataan
tersebut antara lain:“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UU Pencegahan PenodaanAgama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akantetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukanperbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiranatau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yangdianut di Indonesia.”41
Menurut penulis, baik langsung maupun tidak
langsung, baik secara teoritik-konseptual maupun dari
segi praktek dalam pengadilan, delik penodaan agama tidak
38 LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-diteror/, diakses terakhir 15 Oktober 2010; Aisya, Teror,http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=40623816578, diaksesterakhir 15 Oktober 2010.
39 LBH Jakarta di Teror, http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-diteror/
40 http://anbti.org/2010/03/hari-terakhir-persidangan-mahkamah-konstitusi-mengenai-uu-penodaan-agama/
41 Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 287.
dapat dilepaskan dari kebebasan beragama. Dalam kaitan
ini ada semacam kontradiksi dalam logika Mahkamah. Di
satu sisi, Mahkamah menolak mengkaitkan UU Pencegahan
Penodaan Agama dengan kebebasan beragama, namun di sisi
lain Mahkamah mengajukan argumen bahwa kebebasan beragama
tidaklah mutlak, dan UU ini merupakan bentuk pembatasan
terhadap kebebasan beragama.
Salah satu aspek dari argumen MK dalam persoalan
penodaan agama adalah persoalan individualisme dan
komunalisme. Kebebasan beragama merupakan konsep yang
lebih dekat dengan hak individu, sedang konsep penodaan
agama diarahkan untuk melindungi “hak komunal”. Dengan
demikian, tidak mengkaitkan persoalan penodaan agama
dengan kebebasan beragama merupakan cara mengelak dari
perbincangan yang lebih serius. UU Pencegahan Penodaan
Agama merupakan UU yang memang dibuat untuk membatasi
kebebasan seseorang, bukan saja dalam menyangkut cara
mengekspresikan keyakinan (forum eksternum), tapi juga
terkait dengan keyakinan dan penafsiran seseorang atas
agama (forum intenum). Karena itu, yang tidak mutlak bukan
forum eksternum, tapi hal-hal yang masuk kategori forum
internum, seperti soal penafsiran agama, pun tidak mutlak.42
Simaklah kutipan berikut:“Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagiandari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsirantersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama
42 Sulistyowati Irianto, “Mengapa Ditolak Seruan Membawa Bangsa Indonesia YangBerkeadilan Hukum Dan Berkeadilan Sosial?” Makalah dalam Eksaminasi Publik PutusanMahkamah Konstitusi tentang Penolakan terhadap Judicial Review UU No 1/1965tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta: Indonesian LegalResource Center, 9 Agustus 2010.
melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agamayang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehinggakebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifatmutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologiyang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkansumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yangmengancam keamanan dan ketertiban umum apabila
dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam haldemikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan.”43
MK secara eksplisit mangakui bahwa penafsiran
keyakinan atas ajaran agama merupakan kebebasan yang
berada dalam wilayah forum internum. Namun, demi kepentingan
komunal dan politik “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka forum
internum pun bisa dibatasi. Hal ini berbeda dengan doktrin
HAM dan kebebasan beragama internasional yang melarang
intervensi terhadap forum internum. Pada wilayah ini, yang
perlu dilakukan Negara adalah memberi perlindungan agar
hak-hak tersebut tidak diganggu orang lain. Konsep inilah
yang disebut negative rights, yaitu kebebasan dalam bentuknya
yang negatif, yang terdiri dari unsur “bebas untuk”
melakukan berbagai hal yang bisa membuat manusia menjadi
manusia yang bebas. Hukum moralitas atau nilai-nilai
sosial yang mengatur tentang larangan melakukan
intervensi mengandung unsur kebebasan negatif. Aturan
tersebut untuk melindungi hak seseorang dari semua bentuk
intervensi yang dapat mengganggu kebebasannya.44
43 Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, hlm. 288-289.44 Berbeda dengan konsep negative rights adalah positive rights, atau kebebasan
positif. Kebebasan dalam bentuknya yang positif menekankan pada perlunyaintervensi Negara untuk memastikan terwujudnya sebuah bentuk kebebasan yangmenentukan seseorang untuk bisa mengatur bentuk-bentuk kehidupan manusiayang diinginkan. Jika tidak dilakukan intervensi, justru kebebasan itu akanterancam. Lebih jauh lihat Al-Hanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia,(Yogyakarta: Leksbang Grafika, 2010), hlm. 90-91.
Larangan melakukan prosiletisme (penyebaran agama secara
tidak patut) dan penghujatan agama sebenarnya dalam
konteks ini. Kadang-kadang dalam penyebaran agama
dilakukan dengan mengganggu kebebasan orang lain,
sehingga Negara perlu melakukan intervensi dalam bentuk
perlindungan kepada pemeluk agama. Demikian juga larangan
penghujatan agama dimaksudkan untuk melindungi perasaan
keagamaan individu dari kemungkinan dilukai orang lain.
Dengan menghukum proselitisme, sebenarnya Negara melakukan
intervensi terhadap kebebasan individu dalam
memanifestasikan agamanya demi melindungi kebebasan
keagamaan orang lain untuk tidak berpindah agama.
Demikian juga, pemberian hukuman pada pelaku penghujatan
agama, merupakan bentuk intervensi Negara terhadap
kebebasan berekspresi demi melindungi perasaan keagamaan
orang lain.45
Konsep penodaan agama dikacaukan dengan penyataan
kebencian (hatred speech). Untuk menghindari kesalahpahaman,
perlu dirumuskan bahwa penodaan agama hanya terkait
dengan hujatan dan pernyataan kebencian, sehingga aspek
penafsiran keyakinan agama dikeluarkan dari perbincangan
persoalan penodaan agama. Artinya, seseorang tidak bisa
dituduh melakukan penodaan agama hanya karena persoalan
penafsiran keagamaan, meskipun penafsiran tersebut
berbeda, bahkan menyimpang dari pemahaman kebanyakan
orang. Sayangnya, hal ini tidak ditegaskan MK, bahkan MK45 David Llewellyn and H. Victor Conde, “Freedom of Religion or Belief Under
International Humanitarian Law”, dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham (editor),Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Oslo: The Norwegian Centre forHuman Rights, 2004), hlm. 160-163.
meligitimasi adanya delik penodaan agama yang terkait
dengan tafsir keagamaan. Hal inilah yang seharusnya
menjadi sasaran revisi UU Pencegahan Penodaan Agama.
Pembatasan kebebasan beragama hanya terkait dengan
pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan yang bersifat permusuhan, pelecehan dan
terhadap simbol-simbol suatu agama.
Persandingan legal reasoning para pemohon dan
Pertimbangan Putusan Mahkamah, dapat disarikan dalam
matrik berikut46.Matriks
Pendapat Pemohon vs Pendapat Hakim MK
PENDAPAT PEMOHON PENDAPAT HAKIM MAHKAMAHMenyangkut Formalitasnya
Formalitas UU Pencegahan PenodaanAgama bermasalah karena secarahistoris dibentuk dalam keadaandarurat revolusi
Secara materiil UU ini adalahmasih tetap dibutuhkan sebagaipengendali ketertiban umum dalamrangka KUB;
Pembentukan UU PencegahanPenodaan Agama sangat terkaitdengan konteks sosial politik dialam Demokrasi Terpimpin
Manakala norma tersebut masihrelevan pada suatu konteks yanglain, maka ketika itu normatersebut layak dipertahankan
UU Pencegahan Penodaan Agamatidak sah atau harus dinyatakanbatal karena tidak memenuhisyarat pembentukan (uji formal)
UU ini dibuat oleh Pemerintahpada masa Demokrasi Terpimpin,sudah diseleksi melalui KetetapanMPRS Nomor XIX/MPRS/1966, yanghasilnya menyebutkan tetapdiberlakukan sebagai UU.
UU ini cacat formal karena tidaksesuai dengan ketentuan UU No.10Tahun 2004 terutama mengenaisistematika dan hubungan antarapasal-pasal dan penjelasannyaserta lampiran UU
UU No. 10/2004 tidak dapatdijadikan pedoman dalam menilaipembentukan UU yang lahir sebelumlahirnya UU No.10/2004. KedudukanLampiran hanyalah pedoman/arahanyg tidak mutlak diikuti;
Menyangkut Materi Pokok PermohonanPasal 1 UU No.1/PNPS/1965
Rumusan pasal 1 UU ini telah UU ini tidak menentukan
46 Dalam Amar Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 ini, alasan berbeda(concurring opinion) sebagai jalan tengah disampaikan oleh Hakim Harjono.Sedangkan Hakim Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissentingopinion).
menimbulkan ketidakpastian hukumkarena sejumlah frasa seperti“penafsiran yang menyimpang” maupun“pokok-pokok ajaran agama” merupakanklausul yang multitafsir yangdapat digunakan untuk membatasikebebasan beragama orang lain.Penafsiran dan keyakinan beragamaadalah hal yang sangat privat danindividual, sehingga bukanmerupakan kewenangan negara untukmenghakimi keyakinan atau agamaseseorang
pembatasan kebebasan beragama,akan tetapi pembatasan untukmengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang bersifatpermusuhan, penyalahgunaan ataupenodaan terhadap suatu agamaserta pembatasan untuk melakukanpenafsiran atau kegiatan yangmenyimpang dari pokok-pokokajaran agama yang dianut diIndonesia;
Apabila seseorang meyakinisesuatu secara privat danselanjutnya mengkomunikasikaneksistensi spiritual individunyakepada publik merupakan hakasasi. Hal itu merupakan bentukekspresi kebebasan berkeyakinan,berpikir, dan berpendapat yangdijamin UUD 1945;
UU ini tidak melarang untukmelakukan penafsiran terhadapsuatu ajaran agama ataupunmelakukan kegiatan keagamaan yangmenyerupai suatu agama yangdianut di Indonesia secarasendiri-sendiri. Yang dilarangadalah dengan sengaja di mukaumum menceritakan, menganjurkandukungan umum,…
Konsep agama yang diakui atautidak diakui oleh negara darisudut etika politik sebenarnyatidak dibenarkan karena bersifatpragmatis dan negara tidakberkompeten untuk menyatakan haltersebut
Meskipun terdapat keanekaragamanatas aliran agama namun padapokok-pokok agama tetap dapatdirumuskan dan disepakati, dankesepakatan itulah yang menjadikoridor atau ukuran;
Penafsiran ada dalam foruminternum, bersifat subjektifsehingga tidak boleh diintervensioleh negara, karena ada dalamkategori hak berpikir yang tidakboleh dilarang;
Walaupun merupakan forum internum,penafsiran harus tetapberkesesuaian dengan pokok-pokokajaran agama melalui metodologiyang benar berdasarkan sumberajaran agamanya. Jika tidak, akanmenimbulkan reaksi yang mengancamkeamanan/ketertiban umum (dan itumembuka peran negara).
Penafsiran “menyimpang” sangattergantung dari otonomimasyarakat kultural. Yang berhakuntuk mengatakan menyimpang danmenghukum ajaran menyimpangbukanlah sesama manusia melainkanhak Allah sebagai Tuhan.
Setiap agama memiliki pokok-pokokajaran yang diterima umum padainternal agama tersebut, oleh karenaitu yang menentukan pokok-pokokajaran agama adalah pihak internalagama masing-masing.
Negara tidak dapat menentukantafsiran yang benar mengenaiajaran suatu agama;
Negara tidak secara otonommenentukan pokok-pokok ajaranagama dari suatu agama, akantetapi hanya berdasarkan
kesepakatan dari pihak internalagama yang bersangkutan;
UU Pencegahan Penodaan Agamadiskriminatif karena hanyamembatasi pengakuan terhadap enamagama yaitu Islam, Kristen,Katolik, Hindu, Buddha, dan KhongHu Cu;
UU ini tidak membatasipengakuan atau perlindunganhanya terhadap 6 agama, tetapimengakui semua agama yangdianut oleh rakyat Indonesia,sebagaimana Penjelasan Umum UUini;
Makna kata “dibiarkan” yangterdapat di dalam PenjelasanPasal 1 paragraf 3 UU ini harusdiartikan sebagai tidakdihalangi dan bahkan diberi hakuntuk tumbuh dan berkembang,dan bukan dibiarkan dalam artidiabaikan;
Penyebutan agama-agama dalamPenjelasan tersebut hanyalahpengakuan secara faktual-sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia saat UU inidirumuskan;
Negara tidak berhak melakukanintervensi atas tafsiran terhadapkeyakinan atau kepecayaanseseorang untuk tidak mencampuripenafsiran atas agama tertentu;
Beragama sebagai meyakini suatuagama merupakan ranah foruminternum atau kebebasan/HAM.Sedangkan melaksanakan suatukeyakinan adalah forum externumyang terkait dengan HAM oranglain, kepentingan publik, dandengan kepentingan negara
Negara berkepentingan untukmembentuk peraturan per-UU-ansebagai tanggung jawabnya untukmenegakkan dan melindungi HAM.
Jika terdapat isi dari UUD 1945yang tidak sejalan dengankonvensi internasional maka UUD1945 tersebut harus diperbaiki;
Memperbaiki/mengubah isi UUD1945 adalah sepenuhnya wewenangMPR. Mahkamah hanya berwenangmenguji isi UU terhadap UUD1945;
Pasal 1 UU ini yang memberikanlarangan kepada setiap oranguntuk mempublikasikanpenafsiran berbeda dari agamayang dianut di Indonesia adalahbentuk pencegahan darikemungkinan konflik horizontalmasyarakat.
Beragama dalam konteks hakasasi individu tidak dapat
dipisahkan dari hak beragamadlm konteks hak asasi komunal
Pembatasan mengenai nilai-nilaiagama sebagai nilai-nilaikomunal masyarakat adalahpembatasan yang sah menurutkonstitusi.
Pasal 1 UU ini sebagai sebuahpembatasan atas kebebasanberagama.
Pasal 1 UU ini adalah bagiantidak terpisahkan dari maksudperlindungan terhadap hakberagama warga masyarakatIndonesia
Pasal 2 Ayat (1) UU No.1/PNPS/1965Kewenangan memberikan “perintah danperingatan keras” adalah bentuk daripemaksaan (coercion) atas kebebasanberagama yang sejatinya merupakanhak yang melekat dalam dirisetiap manusia;
Negara memang memiliki fungsisebagai pengendali sosial dandiberikan otoritas berdasarkanmandat dari rakyat dan konstitusiuntuk mengatur kehidupanbermasyarakat sesuai dengan UUD1945
Pemaksaan berupa “perintah danperingatan keras” menyebabkan negaraterjebak dalam intervensi ataskebebasan beragama yang merupakanhak asasi yang dijamin oleh UUD1945
Keberadaan SKB merupakan buktidari kehati-hatian dalampelaksanaan kewenangan negarauntuk melakukan tindakan hukumterhadap orang/kelompok yang dianggap menyimpang
SKB tidak memiliki landasan hukumyang tepat untuk menjadi alasanpemaksa untuk melarang keyakinanseseorang atau kelompok yangberbeda dengan keyakinan ataupenafsiran mayoritas
SKB bukanlah peraturan per-UU-an(regeling) melainkan penetapankonkret (beschikking). Tapi terlepasSKB berupa regeling atau beschikking,substansi perintah UU PencegahanPenodaan Agama tentang haltersebut tidak melanggarkonstitusi;
UU ini hanya bisa tegak apabiladilaksanakan bersama tindakan-tindakan fungsional yang kerasdan kadang-kadang diskriminatifterhadap mereka yang berbeda dandituduh menyimpang.
UU ini sudah tepat karena dibuatuntuk melindungi tiga kepentingankepentingan individu,sosial/masyarakat,dan negara),termasuk kepentingan paraPemohon.
Pasal 2 Ayat (2) UU No.1/PNPS/1965Pelarangan yang ditujukan untukmembubarkansebuah organisasi/aliranterlarang adalah bentuk daripengingkaran terhadap kebebasanberserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat sebagaimanayang telah dijamin oleh UUD 1945.
Sebagai tindak lanjut Pasal 2Ayat (1), maka hal tersebutmerupakan ranah kebijakan yangmerupakan penerapan hukum danbukan sebagai permasalahankonstitusional;
para Pemohon telah salahmengartikan kebebasanberserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat sebagaisebuah hak yang tidak dapatdibatasi. Padahal demiketertiban umum maka hak itujuga dapat dibatasi oleh hukumdan diberikan sanksiadministratif
Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965Klausul ‘pemidanaan’ telahmemasuki forum internum dari hakkebebasan beragama dan merupakanketentuan diskriminatif yangbersifat ancaman (threat) danmemaksa (coercion).
Perbedaan penjatuhan pidana yangditetapkan dalam putusanpengadilan bukan merupakan bentukdiskriminasi tapi merupakankewenangan hakim yang dapatmenilai berat/ringannya kasus;
Rumusan pasal a quo bertentangandengan syarat kriminalisasikarena tidak dapat berjalanefektif (unforceable) karena tidakdapat menggambarkan perbuatanyang dilarang dengan teliti(precision principle) sehinggabertentangan dengan prinsipkepastian hukum
Pasal 3 tidak dapat atau dapatditerapkan adalah permasalahanpenerapan hukum dan bukanpermasalahan konstitusional.
Pasal 3 ini tidak dapatdiartikan tersendiri, tapi satukesatuan yang utuh, sehinggajelas prinsip presisinya.
Pasal 3 ini merupakan ultimumremedium manakala sanksiadministrasi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 UU ini tidakefektif;
Proses yudisial yang dilakukanoleh peradilan umum akanmemberikan kepastian penegakanhukum.
Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965Unsur-unsur pemidanaan(“permusuhan” “penyalahgunaan”,atau “penodaan”) yang terdapatdalam Pasal 4 UU ini tidakmengandung kejelasan sehinggabertentangan dengan asaskepastian hukum.
Putusan pengadilan tentangpenjatuhan pidana berdasarkanPasal 156a KUHP yang ternyataberbeda-beda, bukanlah merupakanbentuk ketidakpastian hukum dandiskriminasi, melainkan wujuddari pertimbangan hakim dalammemberikan keadilan sesuai dengankarakteristikkasus masing-masing
D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pola relasi negara-agama di Indonesia memungkinkan
legitimasi delik penodaan agama berdiri di atas prinsip
“Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi poros dari
seluruh sistem hukum di Indonesia. Dalam pandangan MK,
prinsip hukum Indonesia harus dilihat dengan cara
pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama,
serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan
bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan
hubungan antara agama dan negara (separation of state and
religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip
individualisme maupun prinsip komunalisme;
b. Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, kebebasan
beragama/berkeyakinan adalah negatif rights, di mana negara
tidak boleh mencampuri dengan tindakan-tindakan yang
mengurangi, membatasi, dan mencabut kebebasan itu.
Tugas negara adalah menjamin kebebasan. Konstruksi
hukum yang diskriminatif menjadi pemicu sekaligus
landasan berbagai persekusi masyarakat atas setiap
pandangan, keyakinan, dan agama, yang dianggap berbeda
dari mainstream atau dari sudut pandang negara. Namun
demikian, tugas pengelolaan hak oleh negara sangat
diperlukan untuk menetapkan rambu rule of the game guna
menghindari terjadinya conflict of interest.
c. Kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia
menunjukkan bahwa terdapat dua penyebab utama
terjadinya praktik pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan: (1) realitas legal diskriminatif
produk peraturan perundangan-undangan dalam aplikasinya
membuka ruang bagi terjadinya pelapisan pelanggaran;
baik violence by judicial maupun tindakan persekusi yang
didasarkan pada realitas produk hukum yang
diskriminatif; (2) adanya kondisi silent majority dan
masyarakat yang rentan. Silent majority adalah sikap memilih
diam dari sebagian besar masyarakat yang belum
teridentifikasi keberpihakannya;
d. Putusan MK mengenai permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bisa
dibaca sebagai vonis yang mengingatkan setiap pilar
negara dan warga negara untuk membangun cara berfikir,
bersikap, dan berperilaku yang menghargai atau
menghormati hak kebebasan beragama. Berbagai bentuk
penodaan agama seperti radikalisme atas nama agama
merupakan modus berfikir, bersikap, dan berperilaku
yang tidak menghormati hak beragama orang lain.
2. Saran
Fakta-fakta realitas legal diskriminatif dan impunitas
praktik persekusi masyarakat atas kebebasan
beragama/berkeyakinan menuntut adanya pemulihan komunitas
yang menjadi korban pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan, dan merealisasikannya beberapa
rekomendasi, yakni:
a. Bagi DPR RI & Pemerintah, diharapkan dapat merespons
secara arif, aspirasi sebagian masyarakat untuk
merevisi UU No.1/PNPS/1965 secara rasional &
mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap
kelompok-kelompok minoritas;
b. Aparat Penegak Hukum, di satu sisi harus mampu
menerapkan pasal-pasal dalam UU No.1/PNPS/1965 secara
selektif dalam penanganan kasus-kasus terkait ajaran
berbeda/menyimpang dari agama pokok, dan perbedaan
penafsiran. Di sisi lain, ketegasan mengambil tindakan
hukum juga diperlukan terhadap pelaku-pelaku penyebaran
kebencian & permusuhan yang menyebabkan diskriminasi
dan kekerasan terhadap kelompok agama;
c. Masyarakat Sipil, diharuskan untuk mengedepankan
dialog dalam menyikapi perbedaan penafsiran dan ajaran
berbeda/menyimpang dan mengutamakan penegakan hukum
yang berorientasi pada perlindungan kelompok minoritas;
d. Media massa sudah selayaknya untuk meng-endors
jurnalisme damai (peace jounalism) dengan perspektif HAM
untuk selalu berpihak pada kepentingan kelompok
minoritas, cover both side, dan menggunakan istilah-istilah
yang tidak memberikan stigma/prejudice terhadap ajaran-
ajaran yang berbeda/menyimpang dari pokok agama-agama.
Daftar Pustaka
A. Buku & Makalah
____________, 2010. Laporan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2010.Al-Hanif, 2010. Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia,
Leksbang Grafika, Yogyakarta.Azhary, Muhammad Tahir, 1992. Negara Hukum: Studi-studi tentang
Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinyapada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang,Jakarta.
Cranston, Maurice, 1962. What Are Human Rights? Basic Books, NewYork.
Donelly, Jack, 1985. The Concept of Human Rights, St Martin’sPress, New York.
Fatwa, A.M., 1997. “HAM, Pluralsime Agama dan KetahananNasional” Anshari Thayib (ed), HAM dan Pluralisme Agama,Pusat Kajian Strategi dan Kebudayaan, Surabaya.
Hazairin, 1973. Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta.Hazairin, 1974. Tujuh Serangkai tentang Hukum, Tintamas, Jakarta.Intan, Benyamin F. Peraturan Bersama (Perber) Kontraproduktif, Harian
Seputar Indonesia (Sindo), Selasa, 21 September 2010.Irianto, Sulistyowati, “Mengapa Ditolak Seruan Membawa Bangsa
Indonesia Yang Berkeadilan Hukum Dan Berkeadilan Sosial?” Makalahdalam Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusitentang Penolakan terhadap Judicial Review UU No 1/1965tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta:Indonesian Legal Resource Center, 9 Agustus 2010.
Ismail, Faisal, 2008. Sekularisasi: Membongkar Kerancauan PemikiranNurcholis Madjid, Yayasan Nawesea, Yogyakarta.
Llewellyn, David and Victor Conde, H., 2004.“Freedom ofReligion or Belief Under International HumanitarianLaw”, Tore Lindolm, W. Cole Durham (eds.), FacilitatingFreedom of Religion or Belief: A Deskbook, The Norwegian Centre forHuman Rights, Oslo.
Maarif, Ahmad Syafi’i, 1985. Islam dan Masalah Kenegaraan: StudiTentang Percaturan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta.
Madjid, Nurcholis, 1989. Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan,Mizan, Bandung.
Madjid, Nurcholis, 1992. Islam, Doktrin dan Peradaban,YayasanParamadina, Jakarta.
Margiyono, dkk., 2010. Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun LaporanKondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, SetaraInstitute, Jakarta.
Muladi, 2002. Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia, TheHabibie Centre, Jakarta.
Natsir, M., 1992. Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama diIndonesia, Media Dakwah, Jakarta.
Rasjidi, 1977. Koreksi terhadap Drs Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi,Bulan Bintang, Jakarta.
Sihombing, Uli Parulian, dkk., 2008. “Menggugat Bakor Pakem:Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan”, ILRC,Jakarta.
Sjadzali, Munawir, 1990. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah danPemikiran, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.Ketiga, UI-Press, Jakarta.
Sukardja, Ahmad, 1995. Piagam Madinah dan UUD 1945, UniversitasIndonesia Press, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Cet.Kelima, Rajawali Pers, Jakarta.
UNESCO, 1994. Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guidefor Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminaryversion), UNESCO, Paris.
Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002. Hukum, Paradigma, Metode, danDinamika Masalahnya, Ifdhal Kasim (Ed.), ELSAM dan HUMA,Jakarta.
Wignyosoebroto, Soetandyo, 2003. HAM: Konsep dasar danpengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya, dalamKumpulan Tulisan tentang HAM, PUSHAM UNAIR, Surabaya.
B. Pustaka Online
http://www.antaranews.com/berita/1266296609/hasyim-waspadai-gerilya-kelompok-ateis
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.html,
http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/menag-minta-nu-dukung-uupenodaan-agama-17154
http://news.okezone.com/read/2010/03/12/339/312013/ketua-komnas-perempuan-diteriaki-pki
http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-diteror/
http://www.facebook.com/home.php?#!/note.php?note_id=40623816578
http://politik.kompasiana.com/2010/03/17/lbh-jakarta-diteror/
http://anbti.org/2010/03/hari-terakhir-persidangan-mahkamah-konstitusi-mengenai-uu-penodaan-agama/
Biodata Penulis
Arif Hidayat, SHI., SH., MH. lahir di Magelang, Jawa Tengah,
22 Juli 1979. Alumnus Program S2 Konsentrasi Hukum Tata
Negara/Administrasi Negara di UII Jogjakarta tahun 2006. Aktif
menjadi peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) dan Pusat Kajian Hukum,
Otonomi Daerah & Demokrasi (PusHOD). Sekarang menjabat
Direktur Eksekutive Public Defence Institute (P-Dei) Semarang.