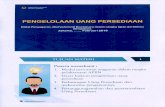up 6 b 22.pdf
-
Upload
stephani-leticia -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
Transcript of up 6 b 22.pdf
Tugas Individu
Kunjungan ke Farm Burung
Unit Pembelajaran VI
Blok 22
STEPHANI LETICIA
10/300640/KH/06677
Kelompok 7
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
1
LEARNING OBJECTIVES
1. Mengetahui standar biosecurity pada pemeliharaan burung
2. Mengetahui manajemen pemeliharaan pada burung
3. Mengetahui tentang Avian Influenza meliputi etiologi, patogenesis,
gejala klinis, diagnosa, dan terapi
4. Mengetahui pada burug selain Avian Influenza meliputi etiologi,
patogenesis, gejala klinis, diagnosa, dan terapi
1. Standar Biosecurity pada Pemeliharaan Burung
Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahana
pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah
kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Secara umum
biosekuriti memiliki tiga prinsip, yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas, serta
sanitasi dan desinfeksi. Isolasi atau pemisahan burung merupakan tindakan
untuk menciptakan lingkungan dimana burung terlindung dari pembawa
penyakit seperti burung liar, hewan lain, dan manusia. Tindakan isolasi
bisa dilakukan dengan memisahkan burung yang sakit dari yang sehat,
menjauhkan burung dari hewan peliharaan lain, dan memasukan burung ke
dalam kandang. Pada burung yang baru dibeli sebaiknya dipisahkan dulu
selama 21 hari atau tiga minggu sebelum bergabung dengan burung
lainnya. Prinsip biosekuriti yang kedua adalah pengendalian lalu lintas,
yaitu upaya untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke
area kandang. Pengendalian ini meliputi pengendalian lalu lintas manusia,
hewan, peralatan, dan kendaraan yang keluar masuk ke area kandang.
Prinsip ini terutama dilakukan pada penangkaran burung yang besar
(Nugroho, 2011). Prinsip biosekuriti yang ketiga adalah sanitasi dan
desinfeksi, prinsip ini merupakan hal yang paling penting. Kandang
burung harus dibersihkan dari kotoran (feses, makanan, dan minuman
yang tumpah) minimal sehari sekali. Tempat pakan dan minum juga harus
dicuci setiap hari. Desinfeksi kandang dilakukan setiap minggu
2
menggunakan desinfektan yang tidak toksik, tidak mengiritasi, dan tidak
bersifat korosif. Desinfektan yang biasanya digunakan adalah alkohol
70%, ammonium kuartener, dan natrium hipoklorit 1% (pemutih)
(Harrison dan Lightfoot, 2006).
2. Manajemen Pemeliharaan Burung
A. Kandang
Burung yang sering dipelihara adalah kenari. Pada
umumnya kandang kenari terbuat dari bahan kayu berbentuk
persegi panjang dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan
tinggi 40 cm untuk menampung sepasang burung kenari. Di dalam
kandang harus disediakan tempat bertengger minimal 1 buah.
Tenggeran yang baik dibuat dari kayu yang kulitnya agak kasar.
Tempat pakan dan minum dapat terbuat dari bahan plastik dan
harus diletakan agak berjauhan agar makanan tidak mudah terkena
air ketika burung mandi dan minuman juga tidak mudah kotor oleh
sisa-sisa makanan (Sridadi, 2001). Untuk burung-burung
Psittacine, seperti kakatua, ukurna kandang harus disesuaikan
dengan jangkauan sayapnya. Misalnya untuk burung makaw
dengan jangakauan sayap 90 cm maka ukuran kandan minimum
adalah 90 x 90 x 90 cm (Brown dan Chitty, 2004).
B. Pakan
Pakan burung disesuaikan dengan jenis burungnya. Burung
karnivora seperti elang dan rajawali bisa diberikan daging sapi, kelinci,
tikus, atau ayam. Untuk pemakan serangga bisa diberikan kroto (larva
semut). Untuk burung herbivora dapat diberikan sayuran, buah-
buahan, dan biji-bijian (Harrison dan Lightfoot, 2006).
3. Avian Influenza
Avian Influenza (AI) merupakan penyakit infeksius pada unggas
yang disebabkan oleh virus dari genus Influnzavirus A yang merupakan
anggota famili Orthonyxoviridae yang merupakan negative-sense ssRNA.
Permukaan virus ini memiliki dua jenis spike glikoprotein yaitu protein
3
hemaglutinin (HA) dan protein neuroamidase (NA) (MacLahlan dan
Dubovi, 2011). Infeksi virus dimulai ketika virus memasuki sel hospes
setelah terjadi penempelan spike virion dengan reseptor spesifik yang ada
di permukaan sel hospesnya. Spike HA dari virus ini akan beritan dengan
reseptor yang mengandung sialic acid (SA) pada permukaan sel hospes.
Virion akan menyusup ke sitoplasma sel dan akan mengintegrasikan
materi genetiknya di dalam inti sel hospesnya dan bereplikasi membentuk
virion-virion baru yang akan menginfeksi kembali sel-sel di sekitarnya.
Virus bereplikasi di saluran pernapasan, pecernaan, renal, dan organ
reproduksi (Radji, 2006). Pada burung-burung peliharaan yang terinfeksi
AI biasanya tidak menunjukan gejala tetapi menjadi carrier yang
mengeluarkan virus dari nares, mulut, konjunctiva, dan kloaka. Pada
unggas produksi seperti ayam gejala yang terlihat adalah gangguan pada
saluran respirasi (batuk, bersin, ngorok, lakrimasi berlebih), pencernaan
(letargi, diare, penurunan nafsu makan dan minum), urinari, dan organ
reproduksi. Untuk diagnosa dapat menggunakan uji serologis seperti
ELISA dan belum ada pengobatan unutk penyakit ini (Saif et al., 2008).
4. Penyakit pada Burung
A. Canary Pox
Canary pox disebabkan oleh avian pox virus dari genus
Avipoxvirus yang merupakan anggota famili Poxviridae yang memiliki
genom dsDNA (MacLahlan dan Dubovi, 2011). Transmisi penyakit ini
bisa secara kontak langsung dengan burung yang terinfeksi atau secara
tidak langsung dari benda yang terkontaminasi. Selain itu transmisi
juga bisa terjadi melalui nyamuk. Masuknya virus ke tubuh hewan bisa
dengan dua cara yaitu melalui kulit yang terluka atau gigitan nyamuk
dan melalui inhalasi. Penyakit ini memiliki dua bentuk yaitu bentuk
kutaneus dan bentuk diphteritik (pernapasan). Virus yang masuk
melalui jalur kulit biasanya menyebabkan infeksi dalam bentuk
kutaneus, sedangkan yang masuk melalui jalur inhalasi biasanya
menyebabkan bentuk diphteritik. Pada bentuk kutaneus akan terlihat
4
bentukan lesi pada daerah-daerah yang tidak ditumbuhi bulu, seperti di
sekitar mata, kaki, nares, dan paruh. Lesi tersebut berupa papula
dengan diameter 2-4 mm yang kemudian akan berubah menjadi
vesikula yang akan pecah secara spontan kemudian mengering dan
membentuk krusta. Burung yang terinfeksi bentuk kutaneus ini sering
menggarukkan daerah sekitar mata dan paruhnya ke tenggeran, mereka
juga akan mematuk lesi di kakinya hingga berdarah. Pada bentuk
diphteritik, lesi terlihat di mukosa lidah, faring dan laring. Lesi
fibrinosa berwarna abu-abu hingga coklat dan bersifat kaseous. Pada
kasus yang parah, burung akan mengalami kesulitan unutkng menelan
dan mengalami dispnoe. Diagnosa dapat dilakukan dengan melihat
gejal klinis, pemeriksaan histopatologis dimana akan terlihat
hiperplasia pada epidermal serta adanya benda inklusi intrasitoplasmik
yang bersifat eosinofilik (merah). Selain itu juga bisa dengan metode
serologis seperti ELISA dan metode molekuler seperti PCR (Saif et al.,
2008). Untuk tereapi, karena infeksi ini disebabkan oleh virus, maka
belum ada terapi kausatif yang dapat digunakan. Terapi yang biasanya
hanya terapi suportif seperti pemberian antibiotik, pemberian iodin
pada lesi kutaneus dan mukosa, serta pemberian multivitamin
(Harrison dan Lightfoot, 2006).
B. Avian Chlamydophylosis
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydophila pittaci, yaitu
bakteri gram negatif dan hanya dapt bereplikasi secara intraselular.
Bakteri ini memeliki 3 bentuk yang secara morfologis berbeda yaitu
elementary body (EB), reticulate body (RB), dan intermediete body
(IB). EB merupakan bentuk infeksius yang berada di luar sel. EB
berukuran kecil sekitar 200-300 nm dan setiap EB dilapisi oleh
membran sitoplasmik,ruang periplasmik, dan lapisan terluar yang
mengandung lipopolisakarida. EB memasuki sel hospes secara
endositosis dan berubah menjadi RB yang memiliki diameter 1 µm.
RB akan melalukan pembelahan biner di dalam endosom dan
5
mengalami maturasi menjadi IB dengan diameter sekitar 0.3-1.0 mm,
sebelum kemudian menjadi EB kembali dan melisiskan sel hospes.
Bakteri ini masuk ke dalam tubuh hospes melalui inhalasi lalu EB akan
menginvasi sel-sel di saluran pernapasan dan didistribusikan melalui
darah ke organ-organ lain (Quinn et al., 2002). Gejala klinis yang
terlihat bervariasi dan tidak ada gejala yang patognomonik. Pada
kebanyakan kasus infeksi terjadi secara laten tanpa adanya gejala klinis
dan hewan yang terinfeksi akan menjadi carrier. Pada burung yang
terinfeksi parah gejala yang mungkin terlihat adalah bulu kusam,
depresi dan anoreksia. Pada kasus kronis akan terlihat penurunan berat
badan. Gejala awal yang mungkin terdeteksi adalah adanya
konjunctivitis, rhinitis, dan sinusitis dengan leleran jernih, bila terjadi
infeksi sekunder leleran akan menjadi purulen. Selain itu mungkin
teramati dispnoe. Gejala-gejala ini sering kali diikuti dengan feses
yang berwarna hijau terang atau diare yang berwarna hijau
kekuningan. Perubahan patologi yang terjadi adalah pembesaran limpa,
perikarditis, hepar sangat membesar dan biasanya terdapat nekrotik
foki yang kecil, serta pada serosa saluran pernapasan menunjukan
adanya eksudat putih kekuningan. Diagnosa dapat dengan melakukan
radiografi pada hewan untuk melihat adanya pembesaran limpa, hepar,
dan ginjal. Selain itu bisa juga dengan pemeriksaan serologis (ELISA),
isolasi bakteri, dan identifikasi bakteri dengan sampel dari swab
konjunctiva (Brown dan Chitty, 2004). Untuk terapi dapat diberi
antibiotik seperti doxycycline yang dicampur dengan air minum
dengan dosis 280 mg/L air atau disuntikan secara IM dengan dosis 100
mg/kg BB sekali seminggu (Harrison dan Lightfoot, 2006).
6
Daftar Pustaka
Brown, N. Chitty, J. 2004. BSAVA Manual of Psittacine Bird 2nd
Edition.
British Small Animal Veterinary Association. England
Harrison, G. J. Lightfoot, T. L. 2006. Clinical Avian Medicine. Spix
Publishing: Florida
MacLahlan, J. Dubovi, E. 2011. Fenner Veterinary Virology 4th
Edition.
Elsevier. United Kingdom
Nugroho, D. T. 2011. Prinsip Biosecurity. http://pustakavet.wordpress.com
/2011/02/16/prinsip-biosecurity.html [Diakses pada hari Senin, 24
Maret 2014]
Quinn, P. Markey, B. Carter, M. Donnelly, W. Leonard, F. 2002. Veterinary
Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science. USA
Saif, Y. Fadly, A. Glisson, J. McDougald, L. Nolan, L. Swayne, D. 2008.
Disease of Poultry 12th
Edition. Blackwell Publishing. Iowa
Sridadi. 2001. Beternak Kenari dan Permasalahannya. Penerbit Kanisius.
Yogyakarta