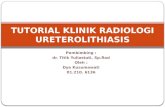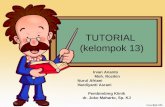Tutorial
-
Upload
susi-susanti -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of Tutorial

LAPORAN PBL SKENARIO B
BLOK VII
Disusun Oleh:
Kelompok VII
Tutor : dr. Nyayu fauzia zen
Vanadia nurul meta 04081001002Ristari Okvaria 04081001017Susi susantI 04081001023Darmawati sahafi 04081001049Nurul fajriah widya U. 04081001053Ari Dwiprasetyo 04081001063 Dwi atika sari 04081001075Carolina Jessica 04081001077Desi oktariana 04081001093Nia Savitri Tamzil 04081001098Netta lionora 04081001104Rudini EffendI 04081001113
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan karunia-
Nya laporan tugas tutorial skenario B ini dapat terselesaikan dengan
baik.
Laporan ini betujuan untuk memenuhi tugas tutorial yang
merupakan bagian dari sistem pembelajaran KBK di Fakultas
Kedokteran Universitas Sriwijaya.
Tim penyusun laporan ini tak lupa mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan
tugas tutorial ini.
Laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan
kritik pembaca akan sangat bermanfaat bagi revisi yang senantiasa
akan tim penyusun lakukan.
Tim Penyusun

DAFTAR ISI
1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar………………………………………....i
3. Daftar Isi……………………………………………...............ii
4. Hasil Tutorial dan Belajar Mandiri :
I. Klarifikasi Istilah……………………………….1
II. Identifikasi Masalah……………………………1
III. Analisis Masalah dan Jawaban…………………1
IV. Hipotesis………………………………………..3
V. Kerangka Konsep……………………………....3
VI. Learning Issues………………………………....4
VII. Sintesis…………………………………………5
Daftar Pustaka……………………………………………...iii
ii

SKENARIO
Tn.lakoni, umur 30 tahun,mengeluh kepada dokter karena sudah 8 hari ini demam terus menerus disertai nyeri ulu hati dan mual dan lidah terasa pahit, sejak lima hari yang lalu tidak BAB.
Dokter memeriksa keadaan umum Tuan lakoni. Pada pemeriksaan fisik dijumpai temperatur 39°C, nadi 88/menit, tensi 110/80 mmHg, RR: 18x/ menit, lidah kotor dan nyeri tekan pada epigastrium. Penderita juga membawa hasil laboratoruim: Hb: 12 mg/dl, leokosit 4500/ mm3 , LED 12mm/ jam , hematokrit 36mg%, trombosit 210.000/mm3, widal test thypii O:1/ 320, parathypii H: 1/640
Kemudian dokter memberikan suntikan sefatoksim intramuskuler tanpa terlebih dahulu melakukan uji alergi, beberapa menit setelah disuntik,Tuan Lakoni tidak sadarkan diri, nadi filiformis, tensi 80/60 mmHg.
Apa saja yang terjadi pada Tuan Lakoni ?
I. Klarifikasi istilah
1. Demam : periksia, peningkatan temperatur tubuh diatas normal2. Nyeri ulu hati : 3. Mual : Sensasi tidak menyenangkan yang secara mengacu pada epigastrium.4. lidah terasa pahit : lidah yang tidak seperti biasanya karna 5. terinfeksi6. nyeri tekan : sensasi yang tidak menyenangkan yang
timbul saat dilakukan tekanan
7. widal test :Uji untuk melihat, aglutinin terhadap antigen O dan H dari S.typhii dan S.para thypii dalam serum penderita yang dicurigai menderita infeksi salmonella
8. Epigastrium : daerah perut bagian tengah dan atas diantara angulus sterni
8. LED : 9. Hematokrit : presentase volume eritrosit dalam darah keseluruhan
10.parathypii :slah satu jenis salmonella penyabab infeksi

11. Suntikan sefatoksin intramuskular: 12. Nadi filiformis :nadi yang bebrbentuk beneng-benang halus 13. Uji alergi : suatu uji yang digunakan untuk menentukan apakah substansi tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi pada individu tertentu 14. Trombosit : sejenis sel darah yang diperlukan untuk pembekuan darah 15. Leukosit :sel darah putih yang merupakan salah satu sistem imun 16. Hb : pigmen pembawa oksigen eritrosit, dibentuk oleh eritrosit yang berkembang dalam sum-sum tulang, merupakan empat rantai polipeptida globin yang berbeda masing-masing terdiri dari beberapa ratus asam amino 17. Tensi : tekanan darah dalam arteri 18. Lidah kotor :
II. Identifikasi masalah
A Tn.lakoni umur 30 tahun mengeluh kepada dokter karena sudah 8 hari ini dia demam terus menerus disertai nyeri ulu hati dan mual dan lidah teraspahit, sejak 5 hari yang lalu tidak BAB.
B Hasil pemeriksaan fisik oleh dokter ditemukan temperatur 39°C, nadi 88/menit, tensi 110/80 mmHg, RR: 18x/ menit, lidah kotor dan nyeritekan pada epigastrium.
C Tuan lakoni juga membawa hasil laboratorium Hb: 12 mg/dl, leokosit 4500/ mm3 , LED 12mm/ jam , hematokrit 36mg%, trombosit 210.000/mm3, widal test thypii O:1/ 320, parathypii H: 1/640. D. Kemudian dokter memberikan suntikan sefatoksim intramuskuler tanpa terlebih dahulu melakukan uji alergi, beberapa menit setelah disuntik,Tuan Lakoni tidak sadarkan diri, nadi filiformis, tensi 80/60 mmHg.
III. Analisis masalah
1. a) Apa penyebab keluhan Tn. Lakoni ?
b) Bagaimana mekanisme demam ?c) Bagaimana mekanisme nyeri ulu hati?d) Bagaiman mekanisme mual dan lidah terasa

pahit? e) Mengapa setelah 3 hari demam, Tn. Lakoni mulai tidak BAB sejak lima hari terakhir ?
2. a) Apa interpretasi pemeriksaan fisik Tn. Lakoni ? b) Mengapa vital sign Tn. Lakoni normal padahal Tn. Lakoni mengalami demam ? c) Bagaimana mekanisme lidah kotor dan histopatologi lidah kotor? d) Bagaiman mekanisme dan penyebab nyeri tekan pada epigastrium ? e) Bagaimana struktur anatomi epigastrium ? f) Bagaimana histology lidah?
3. a) Interpertasi dari pemeriksaan lab ? ( normal & dalam kasus ) b) Apa yang menyebabkan hasil pemeriksaan lab Tn. Lakoni demiikian ? c) Bagaiman widal test ? d) Apa tujuan widal test ? e) Test alternatif apa saja yang dapat digunakan selain widal test ? f) Apa saja diagnosis bandingnya? g) Bagaiman patogenesis penyakit yang dialami Tn. Lakoni ?
4. a) Apa itu suntikan sefatoksim dan fungsinya?
b) Bagaiman aspek farmakodinamik dan farmakokinetik ? c) Bagaimana prosedur uji alergi dan tujuannya? d) Mengapa setelah di suntikan sefatoksim Tn. Lakoni tidak sadarkan diri ? e) Mengapa nadi filiformis ? f) Mengapa tekanan darah 80/ 60 mmHg ? g) Bagaimana penatalaksanaan penyakit Tn. Lakoni ? h) Bagaiman penata laksanaan saat Tn. Lakoni tidak sadarkan diri?
IV Hipotesis

“Tn.lakoni, 30 tahun, mengalami demam thypoid karena infeksi salmonella typhii. dan mengalami syoch anafilaktik karena alergi sefatoksim”
V kerangka konsep
VI. Learning Issue
sebagian dimusnahkan di asam lambung
Sebagian masuk usus halus
Asam lambung meningkat
Masuk ke saluran cernah
Tn. Lakoni, 30 tahun terinfeksi S. tyhpii
mual
Histamin II
Masuk & bersarang dihati & limfe
Degranulasi sel mast
Respon imun
peritonitis
Demam thypoid
Sebagian menembus lamina propriia
Nyeri tekan
perforasi
perdarahan
Sebagian hidup & menetap Masuk aliran limfe
Menembus & masuk aliran darah
Masuk dalam kelenjar limfe mesentrial
Hepatomegali & splenomegali
Diberi suntikan sefataksim
alergen
Syok anafilaltikvasodilatasimediatordegranulasi
IgE and FCR sel mast
IgE
Zat pirogen dilepas oleh leukosit

Learning Issue WhatI know
What I Don’t Know
What I Have to Prove How I will Learn
Demam tifoid
Pemeriksaan fisik & laboratorium
Uji alergi
Farmako kinetic & farmakodinamik sefaoksim
Syok anafilaltik
Histology & histopatologi lidah dan anatomi epigastrium
Definisi
Definisi
Definisi
Definisi
Definisi
Struktur
Etiologi dan patogenesisnyaTest yang digunakan
Manfaat dari uji alergi Pengobatan yang sesuai
Mekanisme terjadinya
Gejalahnya
Penatalaksanaanya
Langkah-langkah dalam
Penatalaksanaannya
Cara mengatasinya
Text book, journal , dan
internet
VII Sintesis
Demam Typhoid
Demam typhoid merupakan infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh
Salmonella typhi, atau jenis yang virulensinya lebih rendah yaitu Salmonella
paratyphi.
Di Indonesia demam typhoid merupakan penyakit endemik yang menular
seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang
wabah, dengan pola penularan yang bersifat sporadik. Dua sumber penularan
demam tifoid adalah pasien dengan demam tifoid dan yang terbanyak adalah
carrier dimana 109 sampai 1011 kuman per gram tinja dikeluarkan oleh mereka.
Media penularan adalah air dan makanan yang tercemar oleh kuman S.typhi.

EPIDEMIOLOGI
Demam tifoid yang tersebar di seluruh dunia tidak tergantung pada iklim.
Demam typhoid terjadi terutama di Negara-negara berkembang dan daerah tropis.
Kebersihan perorangan yang buruk merupakan sumber dari penyakit ini meskipun
lingkungan hidup umumnya adalah baik. Perbaikan sanitasi dan penyediaan
sarana air yang baik dapat mengurangi penyebaran penyakit ini.
Penyebaran Geografis dan Musim
Kasus-kasus demam tifoid terdapat hampir di seluruh bagian dunia.
Penyebarannya tidak bergantung pada iklim maupun musim. Penyakit itu sering
merebak di daerah yang kebersihan lingkungan dan pribadi kurang diperhatikan.
Penyebaran Usia dan Jenis Kelamin
Siapa saja bisa terkena penyakit itu tidak ada perbedaan antara jenis
kelamin lelaki atau perempuan. Umumnya penyakit itu lebih sering diderita anak-
anak. Orang dewasa sering mengalami dengan gejala yang tidak khas, kemudian
menghilang atau sembuh sendiri. Persentase penderita dengan usia di atas 12
tahun seperti bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
Usia Persentase
12 – 30 tahun 70 – 80 %
30 – 40 tahun 10 – 20 %
> 40 tahun 5 – 10 %
a. Etiologi
Demam tifoid dan Paratifoid tipe A, B dan C disebabkan oleh Salmonella
enterica serovoar typhi dan serovoar Paratyphi A, B dan C. Bakteri ini adalah
bakteri gram negatif yang tidak berkapsul, mempunyai flagella sehingga selalu
bergerak dengan menggunakan flagella peritrikosa. Bakteri ini mudah tumbuh
pada perbenihan biasa dan tumbuh baik pada benihan yang mengandung empedu.
Di alam bebas Salmonella typhi dapat betahan hidup lama dalam air, tanah
atau bahkan makanan. Dalam feses di luar tubuh manusia tahan 1-2 bulan. Dalam
air susu dapat berkembang baik dan hidup lebih lama sehingga merupakan batu

locatan untuk penularan penyakitnya. Sumber utama yang terinfeksi adalah
manusia yang selalu mengeluarkan mikroorganisme penyebab penyakit, baik
ketika ia sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan.
Pada masa penyembuhan, penderita masih mengandung Salmonella
didalam kandung empedu atau di dalam ginjal. Sebanyak 5% penderita demam
tifoid kelak akan menjadi karier sementara, sedang 2 % yang lain akan menjadi
karier yang menahun. Sebagian besar dari karier tersebut merupakan karier
intestinal (intestinal type) sedang yang lain termasuk urinary type. Kekambuhan
yang yang ringan pada karier demam tifoid, terutama pada karier jenis intestinal,
sukar diketahui karena gejala dan keluhannya tidak jelas.

Ada 3 macam spesies utama salmonella (salmonella typhi, choleraesuis
dan enteridis). Spesies Salmonella merupakan famili enterobacteriaceae yang
menyebabkan penyakit enterik yang populer. Demam thypoid yang disebabkan
S.Thypi sangat menarik perhatian terutama antigen yang terdapat pada permukaan
kapsulnya. Terdapat empat komponen antigenik penting pada S. Thypi, (1)
capsular Vi polysaccharide yang terletak pada lapisan luar, mengandung 2
kelompok determinan antigen yang memiliki potensi terjadinya reaksi antigen
antibodi, merupakan antigen independen limfosit T dan respon immunnya
dimediasi oleh sel B, (2) lipopolysaccharide (LPS), mengandung 2 determinan
antigen, dikenal dengan endotoksin, merupakan rantai heteropolisakarida unit
oligosakarida (O antigen) terjalin ke inti melalui asam heteroligosakarida (3)
Flagella protein, dikenal sebagai antigen H, mempunyai 2 bentuk fase 1 dan 2,
fase 1 antigennya lebih spesifik untuk S. Thypi, flagella mengandung protein
polimerase yang disebut flagellin yang merupakan bagian penting dalam respon
immun, (4) Outer Membrane Protein (OMPs), proteinnya terdiri dari porin dan
non porin.
b. Transmisi
Demam typhoid ditularkan atau ditransmisikan kebanyakan melalui jalur
fecal-oral. Penyebaran demam typhoid dari orang ke orang sering terjadi pada
lingkungan yang tidak higienis dan pada lingkungan dengan jumlah penduduk
yang padat, hal ini dikarenakan pola penyebaran kuman S.typhi melalui makanan
dan minuman yang terkontaminasi biasanya melalui feses penderita. Penularan
Salmonella Thypi dapat ditularkan melalui berbagai cara, yang dikenal dengan
5F yaitu Food(makanan), Fingers(jari tangan/kuku), Fomitus (muntah),
Fly(lalat), dan melalui Feses. Feses dan muntah pada penderita typhoid dapat
menularkan kuman Salmonella Thypi kepada orang lain.
Kuman tersebut dapat ditularkan melalui perantara lalat, dimana lalat akan
hinggap dimakanan yang akan dikonsumsi oleh orang yang sehat. Apabila orang
tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya seperti mencuci tangan dan
makanan yang tercemar kuman Salmonella Thypi masuk ke tubuh orang yang

sehat melalui mulut. Seperti yang sudah disebutkan, transmisi terjadi melalui
makanan dan minuman yang terkontaminasi salmonella thypi yang masuk ke
dalam tubuh manusia. Bila terpapar S. Thypi sebanyak 105, potensi serangan
relatif ringan dengan masa inkubasi yang panjang. Dengan meningkatnya
organisme atau > 109 potensi serangan meningkat menjadi 95% dengan masa
inkubasi yang lebih singkat. Transmisi di negara berkembang terjadi secara water-
borne dan food-borne.2
Demam tifoid pada umumnya menyerang penderita kelompok umur 5 – 30
tahun, laki – laki sama dengan wanita resikonya terinfeksi. Jarang pada umur
dibawah 2 tahun maupun diatas 60. Pada anak-anak hal ini dikarenakan antibodi
yang belum terbentuk sempurna dan dari segi sosial, pola makanan anak-anak
tidak baik yang didapat di lingkungan. Pada populasi orang muda, penyebaran
demam typhoid dapat disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak
mempertimbangkan faktor kebersihan dan tidak terbiasanya mencuci tangan
sebelum makan.
c. Faktor Risiko
Faktor resikonya adalah orang dengan status imunocompromised dan
orang dengan produksi asam lambung yang terdepresi baik dibuat, misalnya pada
pengguna antasida, H2 blocker, PPI, maupun didapat, misalnya orang dengan
achlorhydia akibat proses penuaan
d. Patogenesis dan pertahanan tubuh( imunitas )
Masuknya kuman Salmonella typhi (S.Typhi) dan Salmonella parathypi
(S.Parathypi) ke dalam tubuh manusia terjadi melalui mekanisme makanan yang
terkontaminasi kuman. Sebagian kuman dimusnahkan dalam lambung karena
lambung menghasilkan HCl, namun sebagian lolos masuk ke dalam usus dan
selanjutnya berkembang biak. Imunitas atau kekebalan adalah sistem
mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis
luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini
mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas, organisme akan

melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus sampai cacing parasit, serta
menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme
yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasa. Deteksi sistem ini
sulit karena adaptasi patogen dan memiliki cara baru agar dapat menginfeksi
organisme
Sistem kekebalan tubuh melindungi organisme dari infekso dengan lapisan
pelindung kekhususan yang meningkat. Pelindung fisikal mencegah patogen
seperti bakteri dan virus memasuki tubuh. Jika patogen melewati pelindung
tersebut, sistem imun bawaan menyediakan perlindungan dengan segera, tetapi
respon tidak-spesifik. Sistem imun bawaan ditemukan pada semua jenis tumbuhan
dan binatang. Namun, jika patogen berhasil melewati respon bawaan, vertebrata
memasuki perlindungan lapisan ketiga, yaitu sistem imun adaptif yang diaktivasi
oleh respon bawaan. Disini, sistem imun mengadaptasi respon tersebut selama
infeksi untuk menambah penyadaran patogen tersebut. Respon ini lalu ditahan
setelah patogen dihabiskan pada bentuk memori imunologikal dan menyebabkan
sistem imun adaptif untuk memasang lebih cepat dan serangan yang lebih kuat
setiap patogen tersebut ditemukan.
Komponen imunitasSistem imun bawaan Sistem imun adaptif
Respon tidak spesifik Respon spesifik patogen dan antigenEksposur menyebabkan respon maksimal segara
Perlambatan waktu antara eksposur dan respon maksimal
Komponen imunitas selular dan respon imun humoral
Komponen imunitas selular dan respon imun humoral
Tidak ada memori imunologikalEksposur menyebabkan adanya memori imunologikal
Ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan
Hanya ditemukan pada Gnathostomata

Mekanisme
Bila respon imunitas humoral mukosa (IgA) usus kurang baik, maka
kuman akan menembus sel-sel epitel (terutama sel M) dan selanjutnya ke lamina
propria. Di lamina propria kuman berkembang biak dan difagosit oleh sel-sel
fagosit terutama oleh makrofag. Kuman dapat hidup dan berkembang biak di
dalam makrofag dan selanjutnya dibawa ke plak Peyeri ileum distal dan kemudian
ke kelenjar getah bening mesenterika.
Alergen melekat pada reseptor
spesifik antigen
Jalur sinyal menginduksi
Modifikasi enzimatik asam arakidonat
Eksositosis granul dengan performed mediator.
Aktivasi transkripsional gen sitokin
PG LTProtease
Sitokin ( mis : TNF )
Dilatasi vascular,
kontraksi otot polos.
Kerusakan jaringan
Dilatasi vaskular
Kontraksi otot polos
Inflamasi (pengerahan
leukosit )
Amin Vasoaktif

Selanjutnya melalui duktus torasikum kuman yang terdapat pada makrofag
ini masuk ke dalam sirkulasi darah (mengakibatkan bakterimia pertama yang
asimptomatik) dan menyebar ke seluruh organ retikuloendothelial tubuh terutama
di hati dan limfa. Di organ ini kuman meninggalkan sel-sel fagosit dan kemudian
berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid dan selanjutnya masuk ke dalam
sirkulasi darah lagi sehingga mengakibatkan bakterimia kedua kalinya dengan
disertai tanda-tanda dan gejala penyakit infeksi sistemik
Di dalam hati, kuman masuk ke dalam kandung empedu, berkembang
biak, dan bersama cairan empedu diekskresikan secara intermiten ke lumen
usus.Sebagian kumandikeluarkan melalui feses dan sebagian masuk lagi ke dalam
sirkulasi setelah menembus usus. Proses yang sama terulang kembali, masuknya
kuman salmonella thypii (s.thypii) Adanya antigen dari kuman ini akan
merangsang limfosit T mengeluarkan suatu zat berupa Machrophage activating
factor (MAF) yang mempengaruhi perubahan morfologi pada makrofag dan
mengakibatkan metabolisme yang sangat aktif, lebih giat lagi mematikan dan
mencerna bakteri. Makrofag pada keadaan ini disebut angry machrophage. Pada
mulanya kuman Salmonella typhi sangat sukar difagositosis karena melindungi
kapsel Vi, baru setelah beberapa lama kuman berada di dalam tubuh penderita
terjadi perubahan pada kapsel Vi, (tidak diketahui sebabnya) sehingga kumannya
sekarang difagositosis oleh makrofag., berhubung makrofag telah teraktivasi dan
hiperaktif maka saat fagositosis kuman Salmonella terjadi pelepasan beberapa
mediator inflamasi yang selanjutnya akan menimbulkan gejala reaksi inflamasi
sistemik seperti demam, malaise, mialgia, sakit kepala, sakit perut, instabilitas
vaskuler, gangguan mental, dan koagulasi
Di dalam plak Peyeri makrofag hiperaktif menimbulkan reaksi hiperplasia
jaringan. Perdarahan saluran cerna dapat terjadi akibat erosi pembuluh darah
sekitar plak Peyeri yang sedang mengalami nekrosis dan hiperplasia akibat
akumulasi sel-sel mononuklear di dinding usus. Proses patologi jaringan limfoid
ini dapat berkembang hingga ke lapisan otot, serosa usus, dan dapat menghasilkan
perforasi. Endotoksin dapat menempel di reseptor sel endotel kapiler dengan

akibat timbulnya komplikasi seperti gangguan neuropsikiatrik, kardiovaskular,
pernafasan, dan gangguan organ lainnya.
REAKSI HIPERSENSITIVITAS.
Hipersensitivitas adalah peningkatan reaktivitas atau sensitivitas terhadap
antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Reaksi hipersensitivitas
terdiri atas berbgai kelainan yang heterogen yang dapat dibagi menurut berbagai
cara.
I. Pembagian Reaksi Hipersensitivitas menurut Waktu Timbulnya Reaksi.
a. Reaksi cepat.
Reaksi cepat terjadi dalam hitungan detik, menghilang dalam 2 jam. Ikatan
silang antara allergen dan IgE pada permukaan sel mast menginduksi penglepasan
mediator vasoaktif. Manifestasi reaksi cepat berupa anafilaksis sistemik atau
anafilaksis lokal.
b. Reaksi Intermediet.
Raksi intermediet terjadi setelah beberapa jam dan menghilang dalam 24 jam.
Reaksi ini melibatkan pembentukan kompleks imun IgG dan kerusakan jaringan
melalui aktivitas komplemen dan atau sel NK/ADCC. Manifestasi reaksi
intermediet dapat berupa reaksi transfusi darah dan reaksi arthus lokal.
Reaksi intermediet diawali oleh IgG dan kerusakan jaringan
pejamu yang disebabkan oleh sel neutrofil dan sel NK.
c. Reaksi Lambat.
Reaksi lambat terlihat sampai sekitar 48 jam setelah terjadi pajanan dengan
antigen yang terjadi oleh aktivasi sel Th. Pada DTH, sitokin yang dilepas oelh sel
T mengaktifkan sel efektor makrofag yang menimbulkan kerusakan jaringan.
Contoh reaksi lambat adalah dermatitis kontak, reaksi M.Tuberkulosis dan reaksi
penolakan tandur.
II. Pembagian Reaksi Hipersensitivitas menurut Gell dan Coombs.
a. Tipe 1 ( reaksi IgE ).

Ikatan silang antara antigen dan IgE yang diikat sel mast dan basofil melepas
mediator vasoaktif. Gejalanya anafilaksis, urtikaria, angiodem, mengi, hipotensi,
nausea, muntah, sakit abdomen, diare, ekzem, alergi makanan.
Contoh penisilin dan ß- laktam lain, enzim, antiserum, protamin,
ekstrak allergen, insulin.
b. Tipe 2 ( reaksi sitotoksik/ IgG atau IgM ).
Antbodi terhadap antigen permukaan sel menimbulkan destruksi sel dengan
bantuan komplemen atau ADCC. Gejala agranulositosis, anemia hemolitik,
trombositopenia reaksi transfuse, eritroblastosis fetalis.
Contoh Karbamazepin, fenotiazin, antikonvulsan, sulfonamide, dll.
c. Tipe 3 ( reaksi kompleks imun ).
Kompleks Ab-Ag mengaktifkan komplemen dan respon inflamasi melalui
infiltrasi massif neutrofil. Gejala : panas, urtikaria, atralgia, limfadenopati, serum
sickness, glomerulonefritis, dll.
Contoh : serum xenogenik, penisilin, ß-laktam sterptomisin, dll.
d. Tipe 4 ( reaksi selular ).
Sel Th1 yang disensitasi melepas sitokin yang mengaktifkan makrofag atau sel
Tc yang berperan dalam kerusakan jaringan. Sel Th2 dan Tc menimbulkan respon
sama.
Semula disangka demam dan gejala toksemia pada typhoid disebabkan oleh
endotoksemia. Tetapi berdasarkan penelitian eksperimental disimpulkan bahwa
endotoksemia bukan merupakan penyebab utama demam pada typhoid.
Endotoksemia berperan pada patogenesis typhoid, karena membantu proses
inflamasi lokal pada usus halus. Demam disebabkan karena salmonella thypi dan
endotoksinnya merangsang sintetis dan pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada
jaringan yang meradang
Jenis demam berdasarkan derajat kisaran suhu tubuh saat demam :
1. low grade : 38-39 C / 100,4-102,2 F
2. moderate : 39- 40 C / 102,2- 104 F
3. high grade : > 40 C / > 104 F

4. hyperpyreksia : > 42 C / > 107,6
Mekanisme Demam
Mekanisme mual
Demam
Pengaturan termostat mendadak diubah (dari suhu normal menjadi meningkat)
Induksi panas didaerah termostat hipotalamus
Dilepaskannya zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang
meradangProduksi sitokin ( IL-1,IL-
6,TNFoleh makrofag, neutrofil, sel mast
Produksi prostagladin E2
Infeksi salmonella typhii.,paratyphii, & endoktosi
Suhu naik
demam

Suhu darah < suhu termostat
Terjadi respon otonom yang menyebabkan kenaikan suhu tubuh
simpati aktif vasokontriksi perifer dan
piloereksi vasokontriksi di GI
pusat muntah (MED.Oblong) porsi vaskularisasi >>
menuju otak
- peningkatan saliva
- penurunan tonus lambung kurang suply O2
dan peristaltik
GI lambat / stop bekerja
Mual jumlah asam lambung berlebihan,
Mekanisme nyeri tekan di epigastrium
Kuman salmonella masuk kesaluran cerna
Sebagian masuk kedalam usus halus

Di ileum terminalis membentuk limfoidplaque peyeri
Sebagian menembus lamina propia
Masuk airan limfe & kedalam kelenjar limfe mesentrial
Menembus dan masuk ke aliran darah
Masuk dan bersarang da hati & limfe
Hepatomegdali & splenimegdali
Nyeri tekan
Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan Laboratorium meliputi pemeriksaan hematologi, urinalis, kimia klinik, imunoreologi, mikr-obiologi, dan biologi molekular. Pemeriksaan ini ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosis (adakalanya bahkan menjadi penentu diagnosis), menetapkan prognosis, memantau perjalanan penyakit dan hasil pengobatan serta timbulnya penyulit.
Hematologi
Kadar hemoglobin dapat normal atau menurun bila terjadi penyulit perdarahan usus atau perforasi.
Hitung leukosit sering rendah (leukopenia), tetapi dapat pula normal atau tinggi.
Hitung jenis leukosit: sering neutropenia dengan limfositosis relatif. LED ( Laju Endap Darah ) : Meningkat

Jumlah trombosit normal atau menurun (trombositopenia).
Urinalis
Protein: bervariasi dari negatif sampai positif (akibat demam) Leukosit dan eritrosit normal; bila meningkat kemungkinan terjadi
penyulit.
Kimia Klinik
Enzim hati (SGOT, SGPT) sering meningkat dengan gambaran peradangan sampai hepatitis Akut.
Imunorologi
Widal
Prosedur Uji Widal1. Uji Widal LempengPada uji widal lempeng lokal, 2 tetes (40 ml) pengenceran serum dan 2 tetes suspensi antigen (O,H,PA,dan PB) dicampur dengan pengaduk, Kemudian lempengan kaca diputarperlahan-lahan selama 5 menit di suhu ruangan lalu dibaca dengan mata telanjang 15 cm di atas lampu neon 10 watt atau chaya matahari dekat jendela.
2.Uji TabungSerum penderita diencerkan secara serial dengan larutan salin normal (1/20, 1/40, 1/80,1/160, 1/320, 1/640 dan seterusnya ). Di buat 4 baris pengenceran seperti tersebut di atas Masing-Masing tabung dalam baris diberi antigen dalam volume yang sama yaitu:
a. Baris pertana diberi antigen Ob. Baris kedua diberi antigen Hc. Baris ketiga diberi anrigen PAd. Baris keempat diberi antigen PB
Setelah dikocok dieramkan pada suhu 48-50 C. Untuk tabung O pengeraman dilakukan pengeraman selama 18-24 jam, sedangkan untuk tabung H , PA, PB. Cukup dieramkan selama 2 jam. Di beberapa laboratorium, semua tabung dieramkan pada suhu 37C selama 24 jam.
Pemeriksaan serologi ini ditujukan untuk mendeteksi adanya antibodi (didalam darah) terhadap antigen kuman Samonella typhi / paratyphi (reagen). Uji ini merupakan test kuno yang masih amat popular dan paling sering diminta terutama di negara dimana penyakit ini endemis seperti di Indonesia. Sebagai uji cepat (rapitd test) hasilnya dapat segera diketahui. Hasil positif dinyatakan dengan

adanya aglutinasi. Karena itu antibodi jenis ini dikenal sebagai Febrile agglutinin.
Hasil uji ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat memberikan hasil positif palsu atau negatif palsu. Hasil positif palsu dapat disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain pernah mendapatkan vaksinasi, reaksi silang dengan spesies lain (Enterobacteriaceae sp), reaksi anamnestik (pernah sakit), dan adanya faktor rheumatoid (RF). Hasil negatif palsu dapat disebabkan oleh karena antara lain penderita sudah mendapatkan terapi antibiotika, waktu pengambilan darah kurang dari 1 minggu sakit, keadaan umum pasien yang buruk, dan adanya penyakit imunologik lain.
Diagnosis Demam Tifoid / Paratifoid dinyatakan bila a/titer O = 1/160 , bahkan mungkin sekali nilai batas tersebut harus lebih tinggi mengingat penyakit demam tifoid ini endemis di Indonesia. Titer O meningkat setelah akhir minggu. Melihat hal-hal di atas maka permintaan tes widal ini pada penderita yang baru menderita demam beberapa hari kurang tepat. Bila hasil reaktif (positif) maka kemungkinan besar bukan disebabkan oleh penyakit saat itu tetapi dari kontrak sebelumnya.
Elisa Salmonella typhi/ paratyphi lgG dan lgM
Pemeriksaan ini merupakan uji imunologik yang lebih baru, yang dianggap lebih sensitif dan spesifik dibandingkan uji Widal untuk mendeteksi Demam Tifoid/ Paratifoid. Sebagai tes cepat (Rapid Test) hasilnya juga dapat segera di ketahui. Diagnosis Demam Typhoid/ Paratyphoid dinyatakan 1/ bila lgM positif menandakan infeksi akut; 2/ jika lgG positif menandakan pernah kontak/ pernah terinfeksi/ reinfeksi/ daerah endemik.
Mikrobiologi
Kultur (Gall culture/ Biakan empedu)
Uji ini merupakan baku emas (gold standard) untuk pemeriksaan Demam Typhoid/ paratyphoid. Interpretasi hasil : jika hasil positif maka diagnosis pasti untuk Demam Tifoid/ Paratifoid. Sebalikanya jika hasil negati, belum tentu bukan Demam Tifoid/ Paratifoid, karena hasil biakan negatif palsu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain jumlah darah terlalu sedikit kurang dari 2mL), darah tidak segera dimasukan ke dalam medial Gall (darah dibiarkan membeku dalam spuit sehingga kuman terperangkap di dalam bekuan), saat pengambilan darah masih dalam minggu- 1 sakit, sudah mendapatkan terapi antibiotika, dan sudah mendapat vaksinasi.
Kekurangan uji ini adalah hasilnya tidak dapat segera diketahui karena perlu waktu untuk pertumbuhan kuman (biasanya positif antara 2-7hari, bila belum ada pertumbuhan koloni ditunggu sampai 7 hari). Pilihan bahan spesimen yang

digunakan pada awal sakit adalah darah, kemudian untuk stadium lanjut/ carrier digunakan urin dan tinja.
Biologi molekular.
PCR (Polymerase Chain Reaction) Metode ini mulai banyak dipergunakan. Pada cara ini di lakukan perbanyakan DNA kuman yang kemudian diindentifikasi dengan DNA probe yang spesifik. Kelebihan uji ini dapat mendeteksi kuman yang terdapat dalam jumlah sedikit (sensitifitas tinggi) serta kekhasan (spesifitas) yang tinggi pula. Spesimen yang digunakan dapat berupa darah, urin, cairan tubuh lainnya serta jaringan biopsi.
Ringkasan:
Telah dibahas gejala klinis dan diagnosis laboratorium penyakit demam tifoid yang disebabkan oleh infeksi Salmonella typhoid dan Salmonella paratyphoid. Penyakit ini endemis di Indonesia dan potensial berbahaya dengan penyulit yang dapat menyebabkan kematian. Kemampuan para tenaga medis untuk dapat mendiagnosis dini penting untuk penyembuhan dan pencegahan timbulnya penyulit. Diagnosis laboratorium meliputi pemeriksaan dari hematologi, urinalisis, kimia klinis, imunoserologis, mikrobiologi biakan sampai PCR. Penting untuk mengetahui kelebihan dan disesuaikan dengan waktu (sudah berapa hari sakit saat akan diperiksa) dan jenis bahan spesimen serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.
Tes Alergi
Tes alergi adalah suatu uji yang digunakan untuk menentukan apakah substansi
tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi pada individu tertentu
Penyakit alergi termasuk penyakit genetik atau keturunan, yang disebabkan oleh
antibodi Imunoglobulin E (Ig E). Yang termasuk penyakit alergi adalah :
1. Rinitis alergi, ditandai oleh bersin-bersin, hidung tersumbat, gatal, berair.
2. Konjungtivitis alergi, ditandai oleh mata gatal, merah, berair, kelopak
mata bengkak.
3. Urtikaria (biduran, kaligata), ditandai oleh kulit bentol, merah, gatal.
4. Dermatitis (eksim), ditandai oleh kulit merah, gatal, mengelupas, kasar.
5. Asma, ditandai oleh batuk lama, sesak napas, bunyi mengi waktu
bernapas.
6. Pada saluran pencernaan, ditandai oleh mual, muntah, mules, diare.

Untuk mengetahui seseorang apakah menderita penyakit alergi dapat kita periksa
kadar Ig E dalam darah, maka nilainya lebih besar dari nilai normal (0,1-0,4 ug/ml
dalam serum) atau ambang batas tinggi. Lalu pasien tersebut harus melakukan tes
alergi untuk mengetahui bahan/zat apa yang menyebabkan penyakit alergi
(alergen).
Ada beberapa macam tes alergi, yaitu :
1. Skin Prick Test (Tes tusuk kulit).
Tes ini untuk memeriksa alergi terhadap alergen hirupdanmakanan,
misalnya debu, tungau debu, serpih kulit binatang, udang, kepiting dan lain-lain.
Tes ini dilakukan di kulit lengan bawah sisi dalam, lalu alergen yang diuji
ditusukkan pada kulit dengan menggunakan jarum khusus (panjang mata jarum 2
mm), jadi tidak menimbulkan luka, berdarah di kulit. Hasilnya dapat segera
diketahui dalam waktu 30 menit Bila positif alergi terhadap alergen tertentu akan
timbul bentol merah gatal.
Syarat tes ini :
Pasien harus dalam keadaan sehat dan bebas obat yang mengandung
antihistamin (obat anti alergi) selama 3 – 7 hari, tergantung jenis obatnya.
Umur yang di anjurkan 4 – 50 tahun. Biaya untuk test ini untuk
mendeteksi 33 alergen berkisar antara Rp. 350.000 - Rp. 600.000 tergantung
instansi dan peralatan yang dipakai.
2. PatchTes (Tes Tempel).
Tes ini untuk mengetahui alergi kontak terhadap bahan kimia, pada
penyakit dermatitis atau eksim. Tes ini dilakukan di kulit punggung. Hasil tes
ini baru dapat dibaca setelah 48 jam. Bila positif terhadap bahan kimia tertentu,

akan timbul bercak kemerahan dan melenting pada kulit.
Syarat tes ini :
o Dalam 48 jam, pasien tidak boleh melakukan aktivitas yang
berkeringat, mandi, posisi tidur tertelungkup, punggung tidak boleh
bergesekan.
o 2 hari sebelum tes, tidak boleh minum obat yang mengandung
steroid atau anti bengkak. Daerah pungung harus bebas dari
obat oles, krim atau salep.
Biaya untuk test ini berkisar antara Rp. 350.000
3. RAST (Radio Allergo Sorbent Test).
Tes ini untuk mengetahui alergi terhadap alergen hirup dan makanan. Tes ini
memerlukan sampel serum darah sebanyak 2 cc. Lalu serum darah tersebut
diproses dengan mesin komputerisasi khusus, hasilnya dapat diketahui setelah 4
jam.
Kelebihan tes ini : dapat dilakukan pada usia berapapun, tidak dipengaruhi oleh
obat-obatan.
Biaya untuk test ini berkisar antara Rp. 200.000 - Rp. 300.000 / alergen.
4. Skin Test (Tes kulit).
Tes ini digunakan untuk mengetahui alergi terhadap obat yang disuntikkan.
Dilakukan di kulit lengan bawah dengan cara menyuntikkan obat yang akan di tes
di lapisan bawah kulit. Hasil tes baru dapat dibaca setelah 15 menit. Bila positif
akan timbul bentol, merah, gatal.
5. Tes Provokasi.
Tes ini digunakan untuk mengetahui alergi terhadap obat yang diminum,
makanan, dapat juga untuk alergen hirup, contohnya debu. Tes provokasi untuk

alergen hirup dinamakan tes provokasi bronkial. Tes ini digunakan untuk
penyakit asma dan pilek alergi. Tes provokasi bronkial dan makanan sudah
jarang dipakai, karena tidak nyaman untuk pasien dan berisiko tinggi terjadinya
serangan asma dan syok. tes provokasi bronkial dan tes provokasi makanan
sudah digantikan oleh Skin Prick Test dan IgE spesifik metode RAST.
Untuk tes provokasi obat, menggunakan metode DBPC (Double Blind Placebo
Control) atau uji samar ganda. caranya pasien minum obat dengan dosis
dinaikkan secara bertahap, lalu ditunggu reaksinya dengan interval 15 – 30
menit.
Dalam satu hari hanya boleh satu macam obat yang dites, untuk tes terhadap
bahan/zat lainnya harus menunggu 48 jam kemudian. Tujuannya untuk
mengetahui reaksi alergi tipe lambat.
Ada sedikit macam obat yang sudah dapat dites dengan metode RAST.Semua
tes alergi memiliki keakuratan 100 %, dengan syarat persiapan tes harus benar,
dan cara melakukan tes harus tepat dan benar
6. Skala
RAST ratingIgE level (KU/L)
Comment
0 < 0.35ABSENT OR UNDETECTABLE ALLERGEN SPECIFIC IgE
1 0.35 - 0.69 LOW OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
2 0.70 - 3.49 MODERATE LEVEL OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
3 3.50 - 17.49 HIGH LEVEL OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
4 17.50 - 49.99 VERY HIGH LEVEL OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
5 50.0 - 100.00 VERY HIGH LEVEL OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
6 > 100.00EXTREMELY HIGH LEVEL OF ALLERGEN SPECIFIC IgE
Farmakologi
a. Distribusi : luas pada jaringan tubuh dan cairan termasuk aqueous humor, cairan asites dan cairan prostat, tulang; penetrasi CFS baik jika ada inflamasi meningitis; menembus plasenta; masuk kedalam ASI.

b. Metabolisme : sebagian dimetabolisme di hati menjadi metabolit aktif deasetilsefotaksim.
c. Waktu paruh eliminasi :
• Cefotaxim : Neonatus premature < 1 minggu : 5-6 jam; neonatus < 1 minggu : 2-3,4 jam ; Dewasa : 1-1,5 jam; diperpanjang untuk pasien dengan kerusakan hepar dan/atau ginjal
• Desacetylcefotaxime : 1,5-1,9 jam; diperpanjang untuk pasien dengan kerusakan hepar dan/atau ginjal
d. Waktu untuk mencapai konsentrasi puncak plasma : pada pemberian melalui I.M. 30 menit.
e. Ekskresi : melalui urin sebagai zat aktif dan metabolit.
Stabilitas Penyimpanan
Larutan rekonstitusi stabil selama 12-24 jam pada suhu kamar, selama 7-10 hari jika disimpan dalam lemari pendingin dan 13 hari jika disimpan beku. I.V. infuse dalam NS atau D5W stabil : Selama 24 jam pada suhu kamar, 5 hari dilemari pendingin dan 3 minggu jika disimpan beku pada wadah Vianflex
Kontraindikasi
Hipersensitif terhadap sefotaksim, komponen lain dalam sediaan dan sefalosporin lainnya.
Efek Samping
• 1% - 10% :
Kulit : rash, pruritus
Saluran cerna : Saluran cerna : kolitis, diare, mual dan muntah Lokal : sakit pada tempat suntikan <1% :
Anafilaksis dan aritmia (setelah pemberian injeksi I.V kateter pusat), peningkatan BUN, kanidiasis,kreatinin meningkat, eusinophilila, erythema multiforme, demam, sakit kepala, interstitial nephritis, neutropenia, phlebitis, pseudomembranous colitis, sindrom Stevens-Johnson, trombositopenia, transaminases meningkat, toxic epidermal necrolysis, urtikaria, vaginitis.
• Dilaporkan juga adanya reaksi ESO dari sefalosporin lainnya :

Agranulositosis, anemia hemolitik, pendarahan, pancytopenia, disfungsi ginjal, pusing, superinfeksi, toxic nephropathy.
Interaksi
Dengan Obat Lain :
• Probenecid dapat menurunkan eliminasi sefalosporin sehingga meningkatkan konsentrasi sefalosporin dalam darah.
• Kombinasi Furosemid, Amonoglikosida dengan Cefotaxim dapat meningkatkan efek nefrotoksik
Dengan Makanan :
Terhadap Ibu Menyusui : Sefotaksim didistribusikan ke dalam air susu sehingga penggunaannya pada ibu menyusui harus disertai perhatian.
Terhadap Anak-anak :
Terhadap Hasil Laboratorium : Positif pada tes Coombs langsung, positif palsu pada tes glukosa urin menggunakan Cu Sulfat (larutan Benedict, larutan Fehling), positif palsu pada tes kreatinin urin atau serum menggunakan reaksi JaffeParameter Monitoring
Observasi tanda dan gejala anafilaksis selama dosis pertama; CBC dengan differential (terutama pada pemakaian lama).
Bentuk Sediaan
Infus Sebagai Sodium Dilarutkan Dalam D5W 1 g (50 ml), 2 g (50 ml)
Injeksi Bentuk Serbuk Untuk Dilarutkan, Sebagai Sodium 500 mg, 1 g, 2 g, 10 g, 20 g
Claforan 500 mg, 1 g, 2 g, 10 g (Mengandung Sodium 50,5 mg (2,2 mEq) Setiap 1 g)
Peringatan
• Penyesuaian dosis untuk pasien dengan penurunan fungsi ginjal.
• Penggunaan dalam waktu lama dapat mengakibatkan superinfeksi.

• Arithmia dilaporkan terjadi pada pasien yang diberikan injeksi dengan injeksi bolus via central line.
• Pasien dengan riwayat alergi terhadap penisilin khususnya reaksi IgE (anafilaktik, urtikaria)
• Dapat terjadi antibiotic-associated colitis atau colitis secondary menjadi C. difficile
Informasi Pasien
a. Bentuk sediaan yang diberikan :
• Infus sebagai sodium. Dilarutkan dalam D5W : 1g/50mL; 2 g/50 mL
• Injeksi sebagai sodium dalam bentuk serbuk untuk dilarutkan : 500 mg, 1 g, 2 g, 10, 20g.
b. Cara pemakaian :
• Diberikan dengan IVP diatas 3-5 menit.
• I.V. infus intermitten diatas 3-5 menit.
Mekanisme Aksi
Menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan berikatan dengan satu atau lebih ikatan protein - penisilin (penicillin-binding proteins-PBPs) yang selanjutnya akan menghambat tahap transpeptidasi sintesis peptidoglikan dinding sel bakteri sehingga menghambat biosintesis dinding sel. Bakteri akan mengalami lisis karena aktivitas enzim autolitik (autolisin dan murein hidrolase) saat dinding sel bakteri terhambat.
Contoh obat dagang cefotaxim: CEFOTAXIME SODIUM (CLAFORAN)Cefotaxime adalah antibiotik yang cara kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri. Cefotaxime temasuk golongan sefalosporin generasi ke-3 yang bersifat bakterisidal dan resisten terhadap beta-laktamase. Sefalosporin generasi ke-3 memiliki aktivitas yang meningkat melawan gram negatif batang. Sefalosporin termasuk golongan antibiotic beta-laktam, yang menghambat sintesis murein, komponen penyusun peptidoglikan bakteri, sehingga sintesis dinding sel bakteri terhambat. Berikut ini adalah mekanisme kerja sefalosporin:
Obat berikatan dengan reseptor spesifik pada bakteri Obat menghambat sintesis dinding sel dengan menghambat transpeptidase
peptidoglikan Obat mengaktivasi enzim autolitik pada dinding sel yang dapat
menimbulkan lesi yang menyebabkan kematian bakteri

Banyak sefalosporin diekskresi terutama oleh ginjal dan dapat terakumulasi serta menginduksi toksisitas pada insufiensi ginjal.
Cefotaxime memiliki waktu paruh pada plasma selama sekitar 1 jam, dan sebaiknya diberikan setiap 4 atau 8 jam untuk infeksi serius. Obat dimetabolisme in vivo menjadi desacetylcefotaxime, yang kurang aktif melawan mikroorganisme dibandingkan dengan cefotaxime, tapi dapat bekerja secara sinergis.
Farmakokinetik
Pemberian obat secara intramuskular sebanyak dosis tunggal 500 mg atau 1 g Claforan mencapai konsentrasi maksimal pada serum sebesar 11.7-20.5 mcg/mL dalam 30 menit dan kemudian menurun dengan waktu paruh mendekati 1 jam. Sekitar 20-36% injesi intravena 14C-cefotaxime diekskresikan ginjal tetap sebagai cefotaxime dan 15-25% sebagai derivative desacetyl. 2 metabolit lain hasil metabolisme obat (20-25%) juga dieskresikan melalui urin dan sudah kehilangan aktivitas bakterisidalnya.
Indikasi
(1) Infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia, caused by Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (Group A streptococci) dan streptococci lain (tidak termasuk enterococci, e.g., Enterococcus faecalis), Staphylococcus aureus (penicillinase and non-penicillinase producing), Escherichia coli, Klebsiella species, Haemophilus influenzae (termasuk ampicillin resistant strains), Haemophilus parainfluenzae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens2, Enterobacter species, indole positive Proteus and Pseudomonas species (termasuk P. aeruginosa).
(2) Genitourinary infections. Urinary tract infections caused by Enterococcus species, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, (penicillinase and non-penicillinase producing), Citrobacter species, Enterobacter species, Escherichia coli, Klebsiella species, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia marcescens and Pseudomonas species (including P. aeruginosa). Also, uncomplicated gonorrhea (cervical/urethral and rectal) caused by Neisseria gonorrhoeae, including penicillinase producing strains.
(3) Gynecologic infections, including pelvic inflammatory disease, endometritis and pelvic cellulitis caused by Staphylococcus epidermidis, Streptococcus species, Enterococcus species, Enterobacter species, Klebsiella species, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Bacteroides species (including Bacteroides fragilis), Clostridium species, and anaerobic cocci (including Peptostreptococcus species and Peptococcus species) and Fusobacterium species (including F. nucleatum).

(4) Bacteremia/Septicemia caused by Escherichia coli, Klebsiella species, and Serratia marcescens, Staphylococcus aureus and Streptococcus species (including S. pneumonia).
(5) Skin and skin structure infections caused by Staphylococcus aureus (penicillinase and non-penicillinase producing), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes (Group A streptococci) and other streptococci, Enterococcus species, Acinetobacter species, Escherichia coli, Citrobacter species (including C. freundii), Enterobacter species, Klebsiella species, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Pseudomonas species, Serratia marcescens, Bacteroides species, and anaerobic cocci (including Peptostreptococcus species and Peptococcus species).
(6) Intra-abdominal infections including peritonitis caused by Streptococcus species, Escherichia coli, Klebsiella species, Bacteroides species, and anaerobic cocci (including Peptostreptococcus species and Peptococcus species) Proteus mirabilis, and Clostridium species.
(7) Bone and/or joint infections caused by Staphylococcus aureus (penicillinase and non-penicillinase producing strains), Streptococcus species (including S. pyogenes), Pseudomonas species (including P. aeruginosa), and Proteus mirabilis.
(8) Central nervous system infections, e.g., meningitis and ventriculitis, caused by Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli.
Kontraindikasi
Pasien yang menderita hipersensitivitas terhadap cefotaxim atau antibiotic golongan sefalosporin lainnya serta penisilin.
Efek Samping Obat (ESO)
Efek samping obat yang paling sering (lebih besar dari 1%) adalah :
Local (4.3%) – Inflamasi pada tempat injeksi dengan pemberian secara intravena atau nyeri, indurasi, dan nyeri tekan setelah injeksi intramuscular.
Hypersensitivity (2.4%) - Rash, pruritus, fever, eosinophilia, urticaria (lebih jarang) dan anaphylaxis (e.g., angioedema, bronchospasm, malaise possibly culminating in shock).
Gastrointestinal (1.4%) - Colitis, diare, nausea, dan muntah.

I. Interaksi obat
Nefrotoksisitas meningkat jika terdapat pemberian sefalosporin dan aminoglycoside secara konkomitan. Probenecid mempengaruhi transfer tubular dari cephalosporins, yang menghambat ekskresinya dan meningkatkan konsentrasi plasmanya.
II. Dosis dan Administrasi
A. DewasaGUIDELINES FOR DOSAGE OF CLAFORAN
Tipe infeksiDaily Dose
(grams)Frekuensi dan Rute Pemberian
Gonococcal urethritis/ cervicitis in males and females 0.5 0.5 gram IM (single dose)Rectal gonorrhea in females
0.5 0.5 gram IM (single dose)
Rectal gonorrhea in males
1 1 gram IM (single dose)
Uncomplicated infections
2 1 gram every 12 hours IM or IV
Moderate to severe infections
3–6 1–2 grams every 8 hours IM or IV
Infections commonly needingantibiotics in higher dosage(e.g., septicemia) 6–8 2 grams every 6–8 hours IVLife-threatening infections
up to 12 2 grams every 4 hours IV
B. Neonatus, Infant, dan Anak-anak
Neonates (birth to 1 month):
0–1 week of age 50 mg/kg per dose every 12 hours IV 1–4 weeks of age 50 mg/kg per dose every 8 hours IV
Infants and Children (1 month to 12 years):
Untuk yang berat badannya kurang dari 50 kg, dosis harian adalah 50-180 mg/kg IM atau IV per berat badan dibagi meniadi 4-6 kali pemberian dengan dosis yang sama. Dosis yang lebih tinggi hanya digunakan untuk infeksi yang lebih serius atau parah, seperti meningitis. Untuk berat badan 50 kg atau lebih, dapat

digunakan dosis seperi pada orang dewasa, namun dosis maksimum harian tidak boleh melebihi 12 gram.
Sefatoksim
GOLONGAN
GENERIK
Cefotaxime / Na Sefotaksim.
INDIKASI
Infeksi saluran pernafasan bagian bawah, infeksi saluran kemih dan kelamin,
infeksi kulit & jaringan lunak, infeksi dalam perut, infeksi tulang dan sendi,
infeksi susunan saraf pusat, infeksi kandungan, infeksi sesudah operasi,
bakteremia (beredarnya bakteri dalam darah)atau septikemia (keracunan darah
oleh bakteri patogenik dan atau zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut).
KONTRA INDIKASI
Hipersensitif terhadap Sefalosporin.
PERHATIAN
# Hipersensitif terhadap Penisilin.
# Gangguan berat fungsi ginjal, riwayat penyakit lambung-usus terutama kolitis.
# Hamil, menyusui.
Interaksi obat :
- ekskresi diperlambat oleh Probenesid.
- resiko nefrotoksisitas ditingkatkan oleh aminoglikosida dan diuretika poten.
EFEK SAMPING
Gangguan saluran pencernaan; reaksi hipersensitivitas; superinfeksi, rasa
sakit/nyeri pada tempat penyuntikan, flebitis (radang pembuluh balik), leukopenia
yang bersifat sementara, eosinofilia, neutropenia, reaksi alergi (demam,
exhanthema, urticaria), syok anafilaktik (jarang terjadi).
KEMASAN
Vial 1 gram x 2 biji.

DOSIS
# Dewasa :
- dosis lazim : 1 gram tiap 6-8 jam, maksimal : 12 gram/hari.
- infeksi tanpa komplikasi : 1 gram tiap 12 jam.
- infeksi sedang sampai berat : 1-2 gram tiap 6-8 jam.
- infeksi yang mengancam hidup : 2 gram tiap 4 jam.
- gonore : 0,5-1 gram tiap 8 jam atau sebagai dosis tunggal.
# Anak-anak dan bayi : 50-100 mg/kg berat badan/hari dibagi menjadi 3-4 kali
pemberian.
Sintesis syok anafilaktik
Pada kasus pasien diberi suntikan cairan sefatoksim tanpa dilakukan tes alergi
terlebih dahulu. Setelah itu pasien mengalami gagngguan kesadaran, nadi
filiformmis, dan tens 80/60 mmhg. Ini menunjukan baha tuan lakoni mengalami
syok anafilaksis. Syok ini disebabkan karena terjadinya reaksi
alergi(hipersensitifitas tipe 1 ). dimana mekanismenya:
Anaphylaxis (Yunani, Ana = jauh dari dan phylaxis = perlindungan).
Anafilaksis berarti Menghilangkan perlindungan. Anafilaksis adalah reaksi alergi
umum dengan efek pada beberapa sistem organ terutama kardiovaskular, respirasi,
kutan dan gastro intestinal yang merupakan reaksi imunologis yang didahului
dengan terpaparnya alergen yang sebelumnya sudah tersensitisasi. Syok
anafilaktik(= shock anafilactic ) adalah reaksi anafilaksis yang disertai hipotensi
dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Reaksi Anafilaktoid adalah suatu reaksi
anafilaksis yang terjadi tanpa melibatkan antigen-antibodi kompleks. Karena
kemiripan gejala dan tanda biasanya diterapi sebagai anafilaksis.
Reaksi ini termasuk reaksi hipersensitivitas Gell dan Combs tipe 1 atau
rekasi alergi. Reaksi tipe 1 timbul segera setelah tubuh terpajan dengan allergen.
Pada reaksi tipe 1, allergen yang masuk ke tubuh menimbulkan respon imun
berupa produksi IgE dan penyakit alergi seperti rhinitis alergi, asma dan

dermatitis atopi. Urutan kejadian atau mekanisme reaksi tipe 1 melalui beberapa
fase sebagai berikut :
1. Fase Sensitasi.
Waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan IgE sampai diikat
silang oleh reseptor spesifik ( Fcε-R ) pada permukaan sel mast/basofil.
Alergen yang masuk lewat kulit, mukosa, saluran nafas atau saluran
makan di tangkap oleh Makrofag.
Makrofag segera mempresen-tasikan antigen tersebut kepada Limfosit T,
dimana ia akan mensekresikan sitokin (IL-4, IL-13) yang menginduksi
Limfosit B berproliferasi menjadi sel Plasma (Plasmosit). Sel plasma
memproduksi Immunoglobulin E (Ig E) spesifik untuk antigen tersebut. Ig
E ini kemudian terikat pada receptor permukaan sel Mast (Mastosit) dan
basofil.
Skema : Alergen masuk ditangkap makrofag antigen
dipresentasikan ke limfosit T sekresi sitokin oleh sel T induksi
limfosit B sel plasma IgE IgE terikat pada sel mast & basofil.
2. Fase aktivasi.
Waktu yang diperlukan antara pajanan ulang dengan antigen yang
spesifik dan sel mast/basofil melepas isinya yang berisikan granul yang
menimbulkan reaksi. Hal ini terjadi dikarenakan ikatan silang antara IgE
dan antigen. Pada kesempatan lain masuk alergen yang sama ke dalam
tubuh. Alergen yang sama tadi akan diikat oleh Ig E spesifik dan memicu
terjadinya reaksi segera yaitu pelepasan mediator vasoaktif antara lain
histamin, serotonin, bradikinin dan beberapa bahan vasoaktif lain dari
granula yang di sebut dengan istilah Preformed mediators.
Ikatan antigen-antibodi merangsang degradasi asam arakidonat dari
membran sel yang akan menghasilkan Leukotrien (LT) dan Prostaglandin
(PG) yang terjadi beberapa waktu setelah degranulasi yang disebut Newly
formed mediators.

Skema : Alergen sama masuk diikat oleh IgE spesifik pelepasan
mediator vasoaktif dalam granul reaksi.
3. Fase Efektor.
Waktu terjadinya repon yang kompleks ( anafilaksis ) sebagai efek
mediator-mediator yang dilepas sel mast/basofil dengan aktivasi
farmakologik pada organ tertentu. Histamin memberikan efek
bronkokonstriksi, meningkatkan permeabilitas kapiler yang nantinya
menyebabkan edema, sekresi mukus dan vasodilatasi. Serotonin
meningkatkan permeabilitas vaskuler dan Bradikinin menyebabkan
kontraksi otot polos. Platelet activating factor (PAF) berefek
bronchospasme dan meningkatkan permeabilitas vaskuler, agregasi dan
aktivasi trombosit. Beberapa faktor kemotaktik menarik eosinofil dan
neutrofil. Prostaglandin yang dihasilkan menyebabkan bronchokonstriksi,
demikian juga dengan Leukotrien.
SKEMA REAKSI TIPE 1 :
Alergen masuk ditangkap makrofag antigen dipresentasikan ke
limfosit T sekresi sitokin oleh sel T induksi limfosit B sel plasma IgE
IgE terikat pada sel mast & basofil alergen sama masuk terikat silang
dengan IgE spesifik di sel mast degranulasi sel mast dan basofil
penglepasan mediator vasoaktif kontraksi otot polos, permeabilitas vaskuler ↑,
vasodilatasi, kerusakan jaringan, sekresi mukosa gaster, anafilaksis.
Dalam kasus Tn.Lakoni, tekanan darahnya menjadi turun setelah diberi
suntikan sefotaksim intramuscular dikarenakan reaksi anafilaksis yang
menyebabkan degranulasi sel mast dan basofil sehingga terjadi penglepasan
mediator vasoaktif seperti histamin, leukotrien, prostaglandin, dan bradikinin
yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga pembuluh darah
melebar dan tekanan darah menjadi turun.

Setelah itu, Tn.Lakoni menjadi tidak sadar dikarenakan apabila tekanan
darah turun, maka volume darah yang menuju otak pun akan berkurang, sehingga
suplai oksigen menurun yang menyebabkan Tn.Lakoni menjadi tidak sadar.
Ketika terjadi reaksi anafilaksis, juga terjadi peningkatan permeabilitas
vaskuler yang disebabkan juga oleh degranulasi sel mast dan basofil
mengakibatkan ada penglepasan histamine, serotonin, dan PAF ( platelet
activating factor ). Hal ini menyebabkan cairan plasma mudah keluar dari
pembuluh darah sehingga terjadi nadi filiformis.
MEDIATOR REAKSI ANAFILAKSIS.
Sel mast banyak mengandung mediated primer antara lain histamine yang
tersimpan di dalam granul. Sel mast yang diaktifkan juga dapat memproduksi
mediator baru atau sekunder seperti leukotrien dan prostaglandin.
1. Histamin.
Puncak reaksi tipe 1 terjadi dalam 10-15 menit. Pada fase aktivasi
terjadi perubahan dalam membrane sel mast akibat metilasi fosfolipid
yang diikuti influks Ca2+ yang menimbulkan aktivasi fosfolipase. Dalam
fase ini energi terlepas akibat glikolisis dan beberapa enzim diaktifkan dan
menggerakkan granul-granul ke permukaan sel.
Kadar cAMP dan cGMP dalam sel berpengaruh terhadap
degranulasi. Degranulasi sel mast dapat juga disebabkan oleh pengaruh
anafilatoksin, C3a, dan C5a.
2. Prostaglandin dan leukotrien.
Dalam reaksi tipe 1 fase lambat juga ada mediator lain yang
berperan seperti PG dan LT. Fase lambat sering timbul setelah fase cepat
hilang yaitu antara 6-8 jam. PG dan Lt merupakan mediator sekunder yang
kemudian dibentuk dari metabolisme asam arakidonat atas pengaruh
fosfolipase A2. Efek biologisnya timbul lebih lambat, namun lebih
menonjol dan berlangsung lebih lama dibanding dengan histamine.
LT berperan pada bronkokonstriksi, pningkatan permeabilitas
vascular, dan produksi mucus. PGE2 menimbulkan bronkokonstriksi.

3. Sitokin.
Berbagai sitokin dilepas sel mast dan basofil seperti IL-3, IL-4, IL-
5, IL-6, IL-10, IL-13, GSM-CSF, dan TNF-α. Beberapa diantranya
berperan dalam manifestasi klinis tipe 1. Sitokin-sitokin tersebut
mengubah lingkungan mikro dan dapat mengerahkan sel inflamasi seperti
neutrofil dan eosinofil.
IL-4 dan IL-13 meningkatkan produksi IgE oleh sel B. Il-5
berperan dalam pengerahan dan aktivasi eosinofil. Kadar TNF-α yang
tinggi dan dilepas sel mast berperan dalam renjatan anafilaksis.
PENATALAKSANAAN SYOK ANAFILAKSIS.
» Penatalaksanaan Syok Anafilaktik :Penyuntikan Adrenalin 0,3 – 0,5 ml IM bila pasien mengalami
reaksi / syok setelah penyuntikan ( dengan tanda-tanda : sesak,
pingsan, kelainan kulit ).
A. Penanganan Utama dan segera :
1. Hentikan pemberian obat / antigen penyebab.
2. Baringkan penderita dengan posisi tungkai lebih tinggi dari kepala.
3. Berikan Adrenalin 1 : 1000 ( 1 mg/ml )
Segera secara IM pada otot deltoideus, dengan dosis 0,3 – 0,5
ml (anak : 0,01 ml/kgbb), dapat diulang tiap lima menit,
pada tempat suntikan atau sengatan dapat diberikan 0,1 – 0,3
ml
Pemberian adrenalin IV apabila terjadi tidak ada respon pada
pemberian secara IM, atau terjadi kegagalan sirkulasi dan
syok, dengan dosis ( dewasa) : 0,5 ml adrenalin 1 : 1000 ( 1 mg
/ ml ) diencerkan dalam 10 ml larutan garam faali dan
diberikan selama 10 menit.
4. Bebaskan jalan napas dan awasi vital sign ( Tensi, Nadi,
Respirasi ) sampai syok teratasi.

5. Pasang infus dengan larutan Glukosa faali bila tekanan darah
systole kurang dari 100 mmHg.
6. Pemberian oksigen 5-10 L/menit
7. Bila diperlukan rujuk pasien ke RSU terdekat dengan pengawasan
tenaga medis.
B. Penanganan Tambahan :
1. Pemberian Antihistamin :
Difenhidramin injeksi 50 mg, dapat diberikan bila timbul urtikaria.
2. Pemberian Kortikosteroid :
Hydrokortison inj 7 – 10 mg / kg BB, dilanjutkan 5 mg / kg BB
setiap 6 jam atau deksametason 2-6 mg/kgbb. untuk mencegah
reaksi berulang.
Antihistamin dan Kortikosteroid tidak untuk mengatasi syok
anafilaktik.
3. Pemberian Aminofilin IV, 4-7 mg/kgbb selama 10-20 menit bila
terjadi tanda – tanda bronkospasme, dapat diikuti dengan infuse
0,6 mg /kgbb/jam, atau brokodilatator aerosol (terbutalin,
salbutamo ).
C. Penanganan penunjang :
1. Tenangkan penderita, istirahat dan hindarkan pemanasan.
2. Pantau tanda-tanda vital secara ketat sedikitnya pada jam pertama.
PENATALAKSANAAN SYOK ANAFILAKTIK
Anafilaksis merupakan kompleks gejala yang timbul secara mendadak (dapat
sangat berat) sebagai akibat perubahan permeabilitas vaskuler dan hiperaktifitas
bronchial karena kerja dari mediator-mediator endogen yang dihasilkan oleh sel-

sel mast dan basofil akibat stimuli antigen. Jadi anafilaksis merupakan reaksi
antigen-antibodi (reaksi hipersensitivitas).
Penderita yang mengalami syok anafilaksis termasuk dalam kegawatan medis dan
harus segera ditangani, karena dapat dengan segera jatuh ke situasi yang
membahayakan jiwa bahkan fatal.
Pengetahuan tentang prosedur penanganan anafilaksis perlu dipahami dan
dikuasai agar kita dapat bertindak dengan cepat dan tepat saat menjumpai kasus
tersebut, dengan demikian dapat terlindung dari tuntutan hokum karena telah
menjalankan prosedur dengan benar.
II. ETIOLOGI
Banyak bahan yang dapat menimbulkan reaksi anafilaksis dan bahan-bahan
tersebut terutama masuk ke dalam tubuh melalui parenteral, walaupun ada pula
bahan-bahan yang masuk melalui enteral yang dapat menimbulkan reaksi
anafilaksis.
Bahan-bahan yang terlibat antara lain:
1. Antibiotika : penicillin dan derivatnya, sefalosporin, tetrasiklin,
eritromisin, streptomisin.
2. NSAID : salisilat, aminopirin.
3. Narkotik analgetik : morfin, kodein, meprobamat
4. Anestesi local : prokain, lidokain, kokain
5. Anestesi umum : thiopental, propofol
6. Produk darah dan antisera : eritrosit, lekosit, trombosit, gama -globulin,
antitoksin, anti difteri, anti

rabies, anti tetanus, anti
bias ular dan laba-laba.
7. Bahan diagnostic : radiokontras yodium
8. Obat – obat lain : protamin, klorpropamid, besi, yodium, tiasid,
suksinilkolin.
9. Bisa hewan : lebah , lalat kerbau , ular , laba-laba, ubur-ubur.
10. Hormon : insulin, ACTH, ekstrak pituitaria.
11. Enzim dan biologis lain : asetil sistein , tambahan enzim pan- kreas.
12. Ekstra allergen potensial yang dipakai pada desensitisasi : tepung sari,
makanan, bisa hewan.
PATOFISIOLOGI
Antigen masuk ke dalam tubuh dapat melalui bermacam cara yauitu
kontak langsung melalui kulit, inhalasi, saluran cerna dan melalui tusukan /
suntikan. Pada reaksi anafilaksis, kejadian masuknya antigen yang paling sering
adalah melalui tusukan / suntikan.
Begitu memasuki tubuh, antigen akan diikat langsung oleh protein yang
spesifik (seperti albumin). Hasil ikatan ini selanjutnya menempel pada dinding sel
makrofag dan dengan segera akan merangsang membrane sel makrofag untuk
melepaskan sel precursor pembentuk reagen antibody immunoglobulin E atau
reagenic ( IgE) antibody forming precursor cell. Sel-sel precursor ini lalu
mengadakan mitosis dan menghasilkan serta membebaskan antibody IgE yang
spesifik. IgE yang terbebaskan ini akan diikat oleh reseptor spesifik yang berada
pada dinding sel mast dan basofil membentuk reseptor baru yaitu F ab. Reseptor F

ab ini berperan sebagai pengenal dan pengikatbantigen yang sama. Proses yang
berlangsung sampai di sini disebut proses sensitisasi.
Pada suatu saat dimana tubuh kemasukan lagi antigen yang sama, maka
antigen ini akan segera sikenali oleh reseptor F ab yang telah terbentuk dan diikat
membentuk ikatan IgE – Ag. Adanya ikatan ini menyebabkan dinding sel mast
dan basofil mengalami degranulasi dan melepaskan mediator-mediator endogen
seperti histamine, kinin, serotonin, Platelet Activating Factor (PAF). Mediator-
mediator ini selanjutnya menuju dan mempengaruhi sel-sel target yaitu sel otot
polos. Proses merupakan reaksi hipersensitivitas.
Pelepasan endogen tersebut bila berlangsung cepat disebut fase akut dank
arena dapat dilepaskan dalam jumlah yang besar, maka biasanya tidak dapat
diatasi dengan hanya memberikan antihistamin.
Pada saat fase akut ini berlangsung, pada membran sel mast dan basofil
terjadi pula proses yang lain. Fosfolipid yang terdapat di membrane sel mast dan
basofil oleh pengaruh enzim fosfolipase berubah menjadi asam arakidonat dan
kemudian akan menjadi prostaglandin, tromboksan dan leukotrien / SRSA ( Slow
Reacting Substance of Anaphylaxis) yang juga merupakan mediator-mediator
endogen anafilaksis. Karena proses terbentuknya mediator yang terakhir ini lebih
lambat, maka disebut dengan fase lambat anafilaksis.
Melalui mekanisme yang berbeda, bahan yang masuk ke dalam tubuh dapat
lasung mengaktivasi permukaan reseptor sel plasma dan menyebabkan
pembebasan histamine oleh sel mast dan basofil tanpa melalui pembentukan IgE
dan reaksi ikatan IgE-Ag. Proses ini disebut reaksi anafilaktoid, yang memberikan
gejala dan tanda serta akibat yang sama seperti reaksi anafilaksis. Beberapa sistem
yang dapat mengaktivasi dapat dilihat pada table berikut:
PENGARUH MEDIATOR ENDOGEN TERHADAP SEL TARGET

Aktivasi imunologis pada sel plasma menyebabkan perubahan kadar c-
AMP dalam sel, mula-mula kadarnya meningkat kemudian menurun tajam karena
mengalami hidrolisis. Penurunan ini ternyata disertai dengan pelepasan mediator-
mediator. Bila penurunan kadar c-AMP dapat dicegah maka pelepasan mediator
ternyata tidak terjadi.
Pada reaksi anafilaksis, histamine dan mediator lainnya yang terbebaskan
akan mempengaruhi sel target yaitu sel otot polos dan sel lainnya. Akibat yang
ditimbulkan dapat berupa:
1. Terjadinya vasodilatasi sehingga terjadi hipovolemi yang relative.
2. Terjadinya kontraksi dari otot-otot polos seperti spasme bronkus
mengakibatkan sesak nafas, kontraksi vesika urinaria menyebabkan
inkontinensia uri, kontraksi usus menyebabkan diare.
3. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan
edema karena pergeseran cairan dari intravaskuler ke interstisial dan
menyebabkan hipovolemi intravaskuler dan syok. Edema yang
dapat terjadi terutama di kulit, bronkus, epiglottis dan laring.
4. Pada jantung dapat terjadi spasme arteri koronaria dan depresi
miokardium.
5. Terjadinya spasme arteri koronaria dan depresi miokardium yang
bila sangat hebat dapat menyebabkan henti jantung mendadak.
Leukotrin (SRSA) dan tromboksan yang terbebaskan pada fase lambat
dapat menyebabkan bronkokonstriksi yang lebih kuat dibandingkan dengan yang
disebabkan oleh histamine. Prostaglandin selain dapat menyebabkan
bronkokonstriksi juga dapat meningkatkan pelepasan histamine. Peningkatan
pelepasan histamine ini dapat pula disebabkan oleh PAF.
Pengaruh fisiologis dari masing-masing mediator endogen terhadap
permeabilitas kapiler, vasodilatasi, bronkus, arteri koronaria dan miokardium
dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2 : Efek fisiologis mediator anafilaksis
Leukotrienes Histamine Prostaglandin Kinins PAF
Increased capillary
permeability
+ + + + +
Vasodilatation + + + + +
Bronchospasm + + + +
Coronary spasm + + +
Myocardial depression +
GAMBARAN KLINIS
Gejala dan tanda yang diakibatkan oleh reaksi anafilaksis ataupun
anafilaktoid sangat bervariasi, dapat tunggal ataupun kombinasi dari beberapa
gejala. Gambaran klinis yang terjadi tergantung dari caranya antigen masuk,
jumlah dan kecepatan absorbsi dan tingkat hipersensitivitas tubuh.
Saat timbulnya gejala berkisar antara 5 – 60 menit dan biasanya dalam 30
menit pertama. Antigen yang masuk melalui parenteral akan lebih cepat
memberikan reaksi dibandingkan melalui cara lain dan reaksi yang terjadi dapat
bersifat sementara atau terus berlanjut.
Manifestasinya pada tubuh antara lain:
1. Kulit : - eritema
- Urtikaria
- Edema angioneurotik
- Eyeksi konjungtiva
- Pucat
- Sianosis

2. Kardiovaskuler : - Takikardi
- Hipotensi
- syok
3. Respirasi : - Rinitis
- Spasme bronkus
- Obstruksi laring karena edema
4. Gastrointestinal : - Mual
- Muntah
- Abdominal Cramps
- Diare
5. Lain-lain : - Rasa cemas
- Batuk
- Parestesi
- Atralgia
- Kejang-kejang
- Gangguan pembekuan darah
- kesadaran menurun
Umumnya makin cepat timbulnya gejala dan tanda tersebut, makin hebat
anafilaksisnya. Manifestasi yang paling berbahaya adalah pada sistem pernafasan
dan kardiovaskuler.
PENGELOLAAN ANAFILAKSIS
Berbagai macam obat dapat digunakan untuk menanggulangi anafilaksis
tetapi adrenalin / epinefrin masih merupakan obat terpilih untuk reaksi yang hebat.
Adrenalin dapat meningkatkan produksi c-AMP sehingga pelepasan histamine

dan mediator lain dapat dicegah, sedangkan xantin (aminofilin) dapat mencegah
degradasi c-AMP. Oleh karena itu keduanya sangat penting dalam mengatasi
anafilaksis.
Obat-obatan yang digunakan dalam terapi anafilaksis umumnya ditujukan untuk:
1. Menghambat sintesis dan lepasnya mediator. 2. Blokade reseptor jaringan terhadap mediator yang lepas 3. mengembalikan fungsi organ terhadap pengaruh mediator.
HISTOLOGI LIDAHLidah terdiri atas bagian yang mudah bergerak
(badan yang terletak di dalam rongga mulut, dan pangkalnya atau akarnya yang melekat pada dasar mulut da membentuk bagian dinding depan faring. Pada permukaan atas atau dorsal lidah terdapat alur berbentuk “V” yaitu sulkus terminalis, yang ujung “V” nya mengarah posterior. Sulkus ini membagi lidah menjadi bagian anterior dan bagian posterior. Sebagian besar lidah terdiri atas serat-serat otot rangka diliputi selaput lender dan mengandung kelelnjar. Serat otot lidah ada yang
intrinsic, yakni yang terdapat di dalam lidah dan ada yang ekstrinsik: yaitu yang lainnya yang berorigo di luar terutama pada mandibula, tulang hyoid, dan berinsersi pada lidah. Di antara serat-serat otot terdapat kelenjar-kelenjar. Kelenjar- kelenjar tersebut terutama yang bersifat mukosa terdapat pada pangkal lidah, dengan saluran keluar bermuara di belakang sulkus terminalis. Kelnjar serosa terletak pada badan lidah, dengan saluran keluar bermuara di depan sulkus (dekat papilla sirkumvalata); sedangkan asini campur terletak di ujung lidah, dengan salurannya bermuara pada permukaan bawah lidah.
Permukaan sepertiga belakang lidah sifatnya nodular, tidak rata oleh karena adanya nodulus limfatikus (tonsila lingua). Di antara tonjolan-tonjolan permukaan epitel terdapat celah-celah disebut kriptus. Di sisni epitel diinfiltrasi oleh banyak limfosit.
Membran mukosa pada permukaan bawah lidah sifatnya licin dan di bawahnya terdapat tunika submukosa. Pada permukaan atas terlihat banyak
Tonsila LinguaTonsila lingua terdapat pada pangkal lidah di belakang papilla sirkumvalata. Tonsila ini terdiri atas kumpulan-kumpulan sumur epithelial yang bermuara lebar dan masing-masing dikelilingi oleh jaringan limfoid. Tiap sumur atau kriptus tunggal dilapisi oleh lanjutan epitel permukaan yaitu epitel berlapis gepeng. Jaringan limfoid berisi selapis limfonodulus, seringkali dengan pusat germinal. Kebanyakan kriptus ditandai oleh sebukan limfosit yang mencolok pada epitel. Saluran keluar kelenjar

tonjolan-tonjolan kecil disebut papil lidah, yang memberikan kesan kasar pada lidah. Terdapat empat jenis papil:
1. Papila filiformis terdapat di atas seluruh permukaan lidah, umumnya tersusun dalam barisan-barisan sejajar dengan sulkus terminalis. Papila filiformis bentuknya kurang lebih seperti kerucut, langsing dan tingginya 2-3 mm. Bagian tengahnya terdiri atas jaringan ikat lamina propria. Jaringan ikat ini juga membentuk papil sekunder. Epitel yang meliputi papila sebagian mengalami pertandukan yang cukup keras sifatnya.
2. Papila fungiformis letaknya tersebar di antara deretan papilla filiformis, dan jumlahnya makin banyak ke arah ujung lidah. Bentuknya seperti jamur dengan tangkai pendek, dan bagian atas yang lebih lebar. Jaringan ikat di tengah-tengah papil membentuk papil sekunder sedangkan epitel di attasnya tipis sehingga pleksus pembuluh darah di dalam lamina propria menyebabkannya berwarna merah atau merah mudah. Kuncup kecap terdapat di dalam epitel.
3. Papila sirkumvalata (vallum= dinding) pada manusia jumlahnya hnaya 10 dmapau 14, dan letaknya di sepanjang sulkus terminalis. Tiap papil menonjol sedikit di tas permukaan dan dibatasi oleh suatu parit melingkar dengan banyak kuncup kecap pada epitel dinding lateralnya. Saluran keluar kelenjar serosa (kelenjar Ebner) bermuara pada dasar alur itu. Kelenjarnya sendiri terletak pada lapisan yang lebih dalam. Sekret serosa cair kelenjar tersebut membersihkan parit dari sisa bahan makanan sehingga memungkinkan penerimaan rangsang kecap baru oleh kuncup kecap .
4. Papila Foliata terletak pada bagian samping dan belakang lidah , berbentuk lipatan -lipatan mirip daun , dengan kucup kecap di dalam epitel lekukan yang terdapat di lipatan . Sama seperti pada papila sirkumvalata kelenjar –kelencar serosa bermuara pada dasar alur .
Lidah kotor. Bagian tengah berwarna putih dan pinggirnya merah. Lidah yang kotor disebabkan karena adanya pembatasan gerakan lidah sehingga papila filiformis yang normalnya mengalami deskuamasi, tidak mengalami deskuamasi dan memanjang. Hal ini menyebabkan banyak debris makanan yang tertinggal dan mengubah
warna dari lidah.
ANATOMI EPIGASTRIUMDari gambar dapat diketahui bahwa pada regio epigastrium terdapat sebagian organ hati. Lambung dan esofagus.

DAFTAR PUSTAKA
Baratawijaya, Karnen Garna. 2009. Imunologi Dasar edisi ke delapan. Jakarta :
Balai penerbit FKUI.
Protap pelaksanaan penanggulangan syok anafilaksis puskesmas Bajangkaran.
2005. Klungkung : Dinas Kesehatan Bajangkaran II.
www.medicastore.com
www.mediapenunjangmedis.dikirismanto.com
http://www.mayoclinic.com/health/allergy-tests/MY00131/METHOD=print
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/allergy/test.html
http://en.wikipedia.org/wiki/RAST_test
http://foodallergies.about.com/od/diagnosingfoodallergies/p/rasttestprofile.htm
http://www.diskes.jabarprov.go.id/index.php?
mod=pubInformasiObat&idMenuKiri=45&idSelected=1&idObat=160&page=7