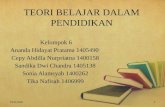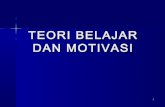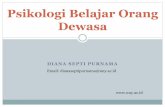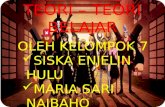Teori Belajar Konstruktivisme.docx
-
Upload
anita-silvia -
Category
Documents
-
view
17 -
download
1
description
Transcript of Teori Belajar Konstruktivisme.docx
BELAJAR DAN PEMBELAJARANKONSTRUKTIVISME DISUSUNOLEH:Anita Silvia (06121410002)Dosen Pengasuh : Drs.A.RachmanIbrahim,M.Sc.EdPROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS SRIWIJAYA2013TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISMEA.Pengertian Teori Belajar KonstruktivismeBelajar menurutkonstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pngertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagaipembelajaranyang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakangagasanyang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyaipengetahuandan menjadi lebih dinamis.Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan membri kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawasiswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata kata mereka sendiri.Dari uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, dimana pesrta didik membina sendiri pengtahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan idea-idea baru dengan kerangka berfikir yang telah ada dan dimilikinya (Shymansky,1992).Dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut peserta didik diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis dan mempunyai kemampuan untuk mengujinya, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dari persoalan yang ditemuinya, mengadakan renungan, mengekspresikan ide dan gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang baru. Teori Konstruktivismedidefinisikan sebagaipembelajaranyang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakangagasanyang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyaipengetahuandan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti:Pelajaraktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalamteoriini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkaninformasibaru dengan pemahamannya yang sudah ada.Ketidakseimbangan merupakan faktormotivasipembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuanilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik miknat pelajar.Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata lain, belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, belajar menurut konstruktivis merupakan upaya keras yang sangat personal, sedangkan internalisasi konsep, hukum, dan prinsip-prinsip umum sebagai konsekuensinya seharusnya diaplikasikan dalam konteks dunia nyata. Guru bertindak sebagai fasilitator yang meyakinkan siswa untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip dan mengkonstruksi pengetahuan dengan memecahkan problem-problem yang realstis. Konstruktivisme juga dikenal sebagai konstruksi pengetahuan sebagai suatu proses sosial. Kita dapat melakukan klarifikasi dan mengorganisasi gagasan mereka sehingga kita dapat menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini akan memberi kesempatan kepada kita mengelaborasi apa yang mereka pelajari. Kita menjadi terbuka terhadap pandangan orang lain Hal ini juga memungkinkan kita menemukan kejanggalan dan inkonsistensi karena dengan belajar kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Konstruktivisme dengan sendirinya memiliki banyak variasi, seperti Generative Learning, Discovery Learning, dan knowledge building. Mengabaikan variasi yang ada, konstruktivisme membangkitkan kebebasan eksplorasi siswa dalam suatu kerangka atau struktur.Dalam sudut pandang laiinya. konstruktivisme merupakan seperangkat asumsi tentang keadaan alami belajar dari manusia yang membimbing para konstruktivis mempelajari teori metode mengajar dalam pendidikan. Nilai-nilai konstruktivisme berkembang dalam pembelajaran yang didukung oleh guru secara memadai berdasarkan inisiatif dan arahan dari siswa sendiri.Ada istilah lain yang sering disalahartikan sama dengan konstruktivisme, yaitu maturationisme. Konstruktivisme (yang merupakan perkembangan kognitif) merupakan suatu aliran yang yang didasarkan pada gagasan bahwa proses dialektika atau interaksi dari perkembangan dan pembelajaran melalui konstruksi aktif dari siswa sendiri yang difasilitasi dan dipromosikan oleh orang dewasa Sedangkan, Aliran maturationisme romantik didasarkan pada gagasan bahwa perkembangan alami siswa dapat terjadi tanpa intervensi orang dewasa dalam lingkungan yang penuh kebebasan (DeVries et al., 2002).
Berkaitan dengan konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang dikaji dan dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, yang dapat diuraikan sebagai berikut:B. Teori Belajar Konstruktivisme Jean PiagetPiaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 1989: 159) menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai denganskematayang dimilikinya.Proses mengkonstruksi, sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut:a)SkemataSekumpulan konsep yang digunakanketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema (schema). Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki empat dan kelinci berkaki dua. Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah dalam struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki empat dan binatang berkaki dua. Semakin dewasa anak, maka semakin sempunalah skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan sekema dilakukan melalui prosesasimilasidanakomodasi.b)AsimilasiAsimilasiadalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan/pergantian skemata melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru pengertian orang itu berkembang.c)AkomodasiDalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi tejadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu.d)KeseimbanganEkuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan dimana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi, ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya.2. Teori Tahapan Perkembangan Anak dari PiagetSelama berabad-abad yang lalu gagasan konstruktivis kurang berkembang secara luas disebabkan persepsi yang umum pada waktu itu bahwa kegiatan bermain yang dilakukan siswa dalam pembelajaran tampaknya kurang penting atau yang lebih parah dianggap tidak dapat mencapai apapun. Jean Piaget tidak setuju dengan pandangan tradisional ini. Ia memandang kegiatan bermain sebagai sesuatu yang penting dan sangat diperlukan sebagai bagian dari perkembangan kognitif siswa. Untuk mendukung pandangannya tersebut, Piaget mengajukan bukti ilmiah. Pada saat ini, teori konstruktivisme sangat mempengaruhi seluruh sektor pendidikan bahkan sektor pendidikan informal.Menurut Ernst von Glasersfeld (1996), Jean Piaget adalah pelopor terbesar teori konstruktivisme yang diketahui serta konstruktivis paling produktif di abad ini. Namun apabila kita telusuri, jauh sebelumnya konstruktivisme sebagai gagasan sudah dilontarkan oleh banyak tokoh pendidikan. Gredler (2001) mengkategorikan Piaget sebagai konstruktivis radikal karena menganggap bahwa konstruktivisme radikal muncul secara langsung sebagai akibat dari teori Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif anak. Meskipun tidak ada teori perkembangan kognitif yang umum, teori yang paling bersejarah dan berpengaruh adalah teori yang dikembangkan oleh Jean Piaget, Psikolog berkebangsaan Swiss (1896-1980). Teorinya berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi perkembangan dan berkenaan dengan pertumbuhan intelegensi, yang untuk Piaget, berarti kemampuan untuk secara lebih akurat merepresentasikan dunia, dan dan mengerjakan operasi-operasi logis dari representasi-representasi konsep realitas dunia. Teori ini memiliki fokus perhatian pada bangkitnya dan dimilikinya schemataskema bagaimana seseorang mengenal duniadalam saat tingkatan-tingkatan perkembangan, ketika anak-anak menerima cara baru bagaimana secara mental merepresentasikan informasi. Teori ini dianggap konstruktivis, yang berarti bahwa, tidak seperti teori nativis (yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif sebagai perkembangan dari pengetahuan dan kemampuan bawaan) ataupun teori empiris (yang berpendapat bahwa perkembangan kognitif sebagai perolehan gradual dari pengetahuan melalui pengalaman), teori ini berpendapat bahwa kita mengkonstruksi kemampuan kognitif kita melalui kegiatan motivasi-diri dalam dunia nyata. Karena teorinya ini, Piaget mendapatkan Penghargaan Erasmus.Piaget membagi skema Anak dalam menggunakan pemahamannya untuk memahami dunia mealui empat tahapan utama, yang secara umum berkorelasi dengan dan semakin bertambah canggih sejalan dengan bertambahnya usia:a. Tahapan Sensorimotor (Usia 0-2 tahun)Menurut Piaget, anak dalam tahapan sensorimotor lebih mengutamakan mengeksplorasi dunia nyata dengan perasaan dibandingkan dengan melalui operasi mental. Bayi terlahir dengan seperangkat refleks yang sama, menurut Piaget, sebagai tambahan dorongan untuk melakukan eksplorasi terhadap dunia nyata. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks-refleks yang sama tersebut (lihat asimilasi dan akomodasi di bagian berikut). Tahapan sensorimotor merupakan tahapan paling awal dari empat tahapan. Menurut Piaget, tahapan ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan spasial esensial dan pemahaman dari dunia nyata yang terdiri dari enam sub-tahapan. Sub-tahapan pertama terjadi dari kelahiran sampai dengan enam minggu dan berasosiasi terutama dengan perkembangan refleks. Tiga refleks utama dideskripsikan oleh Piaget: memasukkan objek-objek ke mulut, mengikuti pandangan mata ke objek begerak atau objek menarik, dan mengepalkan tangan ketika suatu objek kontak dengan telapak tangan. Selama enam minggu kehidupan awal, refleks-refleks ini mulai menjadi kegiatan yang disadari; sebagai contoh, refleks mengepal menjadi gerakan menangkap dengan sengaja. (Gruber and Vaneche, 1977).Sub-tahapan kedua terjadi sejak usia enam minggu sampai empat bulan dan terutama berasosiasi dengan kebiasaan. Ciri utamanya adalah reaksi berulang atau pengulangan kegiatan yang pada awalnya hanya melibatkan satu bagian tubuhnya saja. Contoh dari tipe reaksi ini antara lain mencakup seorang bayi berulang-ulang menggerakkan tangannya di depan wajahnya. Juga pada tahapan ini dimungkinkan dimulainya reaksi pasif, disebabkan oleh classical conditioning atau operant conditioning (Gruber et al., 1977).Sub-tahapan ketiga terjadi mulai bayi berusia empat bulan sampai sembilan bulan dan terutama berasosiasi dengan koordinasi antara pandangan dengan pengenalan melalui indera lainnya. Tiga kemampuan baru mulai dimiliki pada tahapan ini: menggenggam dengan sengaja benda-benda yang diinginkan, reaksi berulang kedua, dan diferensiasi terhadap cara dan keinginan. Pada tahapan ini, seorang bayi menggapai-gapai di udara secara sengaja ke arah suatu objek yang diinginkannya, gerakan lucu yang seringkali sangat disenangi oleh keluarganya. Reaksi berulang kedua, atau pengulangan terhadap suatu gerakan yang melibatkan objek eksternal dimulai: seperti gerakan orang dewasa memencet tombol lampu secara berulang. Ada kemungkinan ini merupakan satu dari tahapan paling penting dari pertumbuhan anak karena ini sangat berarti bagi dimulainya penalaran (Gruber et al., 1977). Bagian paling akhir dari dari sub-tahapan ini adalah bayi mulai memiliki perasaan keberadaan objek secara permanen, semacam melalui tes kesalahan A-bukan-B.Sub-tahapan ke empat terjadi dari usia sembilan sampai dua belas bulan dan berasosiasi terutama dengan perkembangan logika dan koordinasi antara cara dan keinginan. Tahapan ini amat vital dari perkembangan, terjadi apa yang disebut Piaget kecerdasan sebenarnya pertama. Juga, tahapan ini ditandai dengan dimulainya orientasi tujuan, perencanaan besar dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan (Gruber et al. 1977).Sub-tahapan kelima terjadi dari usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berasosiasi terutama dengan penemuan keinginan-keinginan baru untuk mencapai tujuan. Piaget mendeskripsikan anak pada tahapan ini sebagai cendekiawan muda, memulai semacam eksperimen untuk menemukan metode baru dalam menemui tantangan (Gruber et al. 1977).Sub-tahapan ke enam berasosiasi terutama dengan dimulainya wawasan, atau kretivitas yang sesungguhnya. Saat ini menandai transformasi menuju tahapan preoperasional.1) Peranan imitasiPiaget merumuskan kegiatan imitatif merupakan pendahuluan dari simbolisme mental.[1] Aktivitas tubuh, menirukan gerakan dari fenomena yang teramati, pada akhirnya membangun pemberi arti tubuh/perilaku yang tertuju pada fenomena dalam cara yang bisa diperbandingkan dengan simbol-simbol mental yang kemudian akan menjadi fenomena-fenomena tersebut. Bentuk-bentuk imitatif seperti ini memfasilitasi dasar-dasar kegiatan simbolik mental yang terbangun di kemudian hari. Simbolnya adalah, menurut Piaget, suatu imitasi yang terinternalisasi.Bagi Piaget, bahkan persepsi dari suatu objek merupakan aktivitas imitatif; ketika mata melacak bentuk dari suatu objek ia akan membentuk konsep pre-simbolik dari objek tersebut. Piaget mengungkapkan bahwa pengalaman akan berbagai gerakan di sini kemungkinan diulangi oleh anak di dalam suatu peragaan singkat ketika mengingat-ingat objek; Gambaran tubuh ini mensimbolkan objek yang telah dipersepsikan sebelumnya.b. Tahapan Praoperational (Usia 2-7 tahun)Tahapan preoperasional merupakan tahapan kedua dari empat tahapan perkembangan kognitif. Dengan mengamati urutan bermain, Piaget dapat mendemonstrasikan bahwa sampai dengan akhir tahun kedua secara kualitatif terjadi fungsi psikologis jenis baru. Cara bekerja teori aliran Piaget adalah dalam berbagai prosedur peran mental terhadap objek. Ciri pembeda dari tahapan preoperasional adalah operasi mental yang jarang tidak memadai logika.Menurut Piaget, tahapan Pre-Operasional dari perkembangan mengikuti tahapan Sensorimotor dan terjadi antara usia 2-7 tahun. Tahapan ini meliputi beberapa proses: Symbolic functioning (pemfungsian simbol) yang dicirikan oleh penggunaan simbol-simbol mental berupa kata atau gambar yang digunakan anak untuk merepresentasikan sesuatu yang secara fisik tidak ada. Centration (pemusatan) dicirikan oleh fokus atau pemusatan perhatian dari anak pada hanya satu aspek dari stimulus atau situasi. Sebagai contoh, dalam menuangkan sejumlah tertentu cairan dari dari wadah yang sempit ke dalam mangkuk yang dangkal, anak prasekolah kemungkinan menyimpulkan bahwa kuantitas dari cairan telah berkurang, karena menjadi lebih rendahhal ini dikarenakan anak hanya memperhatikan ketinggian air, namun tidak memperhitungkan diameter wadah yang baru. Intuitive thought (pemikiran intuitif)- terjadi ketika anak dapat mempercayai sesuatu tanpa memahami mengapa dia mempercayai itu. Egocentrism suatu jenis centration, yang berarti suatu tendensi dari seorang anak untuk memikirkan hanya sudut pandangnya sendiri saja. Juga, ketidakmampuan anak untuk memahami sudut pandang orang lain. Inability to Conserve (ketidak mampuan berbicara) Melalui eksperimen yang pernah dilakukan Piaget dalam percakapan (pembicaaan tentang massa, volume dan angka) Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak pada tahapan preoperasional memiliki persepsi yang kurang dalam pembicaraan tentang massa, volume, dan angka setelah bentuk aslinya berubah. Sebagai contoh, seorang anak pada tahapan ini akan percaya bahwa roti yang ditata berjajar dengan pola O-O-O-O-O akan memiliki jumlah yang sama dengan roti yang ditata berjajar dengan pola OO-O-OO-O, karena mereka memiliki panjang atau ketinggian yang sama, atau cairan dalam gelas 8-ons yang yang lonjong memiliki cairan yang lebih banyak dibandingkan dengan cairan 8-ons dalam gelas yang melebar (lihat juga centration, di atas).c. Tahapan Operasional Konkret (Usia 7-11 tahun)Tahapan Operasional Konkret merupakan tahapan ketiga dari empat tahapan dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Tahapan ini, yang merupakan kelanjutan dari tahapan Preoperasional, terjadi ketika anak berusia antara 6 dan 11 tahun dan dicirikan oleh penggunan logika yang memadai. Proses penting yang terjadi selama tahapan ini adalah:1) Decentering (tidak memusat)-ketika anak memperhitungkan berbagai aspek dari suatu masalah untuk memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak lagi memiliki persepsi bahwa gelas yang sangat lebar namun pendek dapat menampung cairan lebih sedikit dibandingkan gelas yang lebarnya cukup namun lebih tinggi.2) Reversibility (kemampuan membalik)-ketika seorang anak memahami bahwa jumlah suatu objek dapat berubah, dan mengembalikannya pada keadaan semula. Dalam kondisi demikian, anak dengan cepat dapat memutuskan bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 sama dengan 4, jumlah sebenarnya.3) Conservation (pembicaraan) memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah suatu item tidak berhubungan dengan penyusunan atau kenampakan objek atau item tersebut. Sebagai contoh, ketika pada seorang anak ditunjukkan dua wadah gelas dan mangkuk, ia akan memahami bahwa jika air di dalam gelas dipindahkan ke dalam mangkuk akan berubah ketinggiannya namun sama kuantitasnya dibandingkan dengan wadah sebelumnya.4) Serialisation (serialisasi)-kemampuan merangkai kembali objek secara berurutan berdasarkan ukuran, bentuk, atau karakteristik lain. Sebagai contoh, jika mereka diberi objek dengan gradiasi warna, mereka akan mengenal gradiasi warna tersebut.5) Classification (klasifikasi)-yaitu kemampuan untuk menyebutkan nama dan mengidentifikasi seperangkat objek menurut kenampakannya, ukuran atau karakteristik lainnya, termasuk gagasan bahwa seperangkat objek dapat mencakup objek lainnya. Seorang anak pada tahapan ini tidak lagi menjadi subjek pembatasan yang tidak logis dari animisme (suatu kepercayaan bahwa semua objek adalah binatang dan karenanya memiliki perasaan).6) Elimination of Egocentrism (pembatasan egosentrisme)-kemampuan memandang segala sesuatu dari perspektif orang lain (meskipun jika perpsektif itu tidak benar). Sebagai contoh, perlihatkan seorang anak komik yang memperlihatkan Jane meletakkan sebuah boneka di bawah kotak, meninggalkan ruangan, dan kemudian Jill menggerakkan boneka tersebut ke laci, dan Jane kembali. Seorang anak dalam tahapan konkret operasional akan mengatakan bahwa Jane akan tetap berpikir boneka tersebut di bawah kotak meskipun anak tersebut tahu sesungguhnya bonekanya dalam laci.d. Tahapan operasional formal (Usia 11 tahun-Dewasa)Tahapan Operasional Formal merupakan tahapan keempat dan terakhir dari seluruh tahapan perkembangan kognitif anak dari Teori Piaget. Tahapan ini, yang mengikuti tahapan Operasional Konkret, pada umumnya terjadi di sekitar usia 11 tahun (pubertas) dan berlanjut ke masa kedewasaan. Karakteristik dari tahapan ini yaitu memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan menarik kesimpulan dari informasi yang berhasil diperolehnya. Selama tahapan ini seorang muda memiliki fungsi sebagaimana orang dewasa dan nilai-nilai, rahasia orang dewasa, dan nilai-nilai. Hal ini mudah dimengerti, karena faktor-faktor biologis kemungkinan dapat dilacak dari tahapan ini sebagaimana apa yang terjadi selama masa pubertas dan ditandai masuknya ke masa dewasa dalam Physiology, kognitif, dan penilaian moral (Kohlberg), perkembangan Psychosexual (Freud), dan perkembangan sosial (Erikson). Sekitar dua pertiga dari orang tidak sepenuhnya sukses dalam tahapan ini, dan terpaku pada tahapan operasional konkret.e. Gambaran umum mengenai tahapanDari ke empat tahapan tersebut ditemukan karakteristik berikut ini:1) Meskipun waktunya bervariasi, urutannya sama.2) Berlaku secara universal (tidak dipengaruhi budaya tertentu)3) Dapat digeneralisasikan: operasi yang logis dan representatif yang dialami seorang anak seharusnya meluas ke semua konsep dan isi pengetahuan.4) Tahapan-tahapan secara keseluruhan secara logis.5) Hirarkhi alamiah dari urutan tahapan (setiap tahapan lanjutan merupakan elemen kesatuan dari tahapan sebelumnya, namun lebih bervariasi dan terpadu).6) Tahapan merepresentasikan perbedaan kualitatif dalam model berfikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif.f. Kritik Bagi Teori Tahapan Perkembangan PiagetTeori Piaget tentang perkembangan ini mendapat banyak tantangan dari beberapa aspek. Pertama, Piaget sendiri menyatakan, perkembangan tidak selalu berlangsung dengan cara yang mulus seperti yang diprediksi dalam teorinya. Decalage, atau kesenjangan yang tidak diperkirakan selama berlangsungnya perkembangan, mengungkapkan bahwa model tahapan ini paling baik digunakan sebagai perkiraan.Lebih jauh lagi, teori Piaget merupakan domain umum, memperkirkan bahwa kematangan kognitif terjadi lintas domain yang berbeda secara bersamaan (seperti matematika, logka, pemahaman fisika, bahasa, dsb). Namun demikian, para penganut teori perkembangan kognitif aliran terkini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan dari sains kognitif menjauh dari generalisasi domain dan menuju spesifikasi domain atau modularitas pikiran, yaitu bagian-bagian kognitif yang berbeda kemungkinan sangat independen satu sama lain sehingga berkembang dalam waktu yang amat berbeda. Dalam aliran pemahaman tersebut, para penganut teori perkembangan kognitif aliran terkini memberikan alasan bahwa daripada berada pada domain umum pembelajar, mereka lebih cenderung pada teori yang berpendapat bahwa anak-anak sudah dilengkapi dengan teori domain spesifik, yang lebih sering disebut inti pengetahuan, yang memungkinkan mereka melakukan terobosan dalam belajar dalam domain tersebut. Sebagai contoh, bahkan anak yang masih bayi menunjukkan pemahamannya pada beberapa prinsip dasar fisika (seperti satu objek tidak dapat menembus objek lainnya) dan keinginannya layaknya manusia yang sudah dewasa seseorang (seperti salah satu tanganya secara berulang-ulang menggapai-gapai suatu objek untuk mendpatkan objek tersebut, bukan hanya gerakan tanpa arti, namun lebih sebagai tujuan). Asumsi dasar ini kemungkinan semacam blok-blok bangunan yang menyusun pengetahuan yang telah dikonstruksi sehingga lebih terelaborasi.C.Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky Ratumanan (2004:45) mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berfikir, berkomunikasi dan memecahkan masalah, dengan demikian perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berfikir diri sendiri.Menurut Slavin (Ratumanan, 2004:49) ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinyasettingkelas berbentuk pembelajarankooperatifantar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan terdekat/proksimal masing-masing.Kedua,pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan (scaffolding). Denganscaffolding, semakin lama siswa semakin dapat mengambil tanggungjawab untuk pembelajarannya sendiri.a.Pengelolaan pembelajaranInteraksi sosial individu dengan lingkungannya sengat mempengaruhi perkembanganbelajar seseorang, sehingga perkemkembangan sifat-sifat dan jenis manusia akan dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Menurut Vygotsky dalam Slavin (2000), peserta didik melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual peserta didik.b.Pemberian bimbinganMenurut Vygotsky, tujuan belajar akan tercapai dengan belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari tetapi tugas-tugas tersebut masih berada dalam daerah perkembangan terdekat mereka (Wersch,1985), yaitu tugas-tugas yang terletak di atas peringkat perkembangannya. Menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain.D.Intervensi Konstruktivisme dalam pembelajaran1) Kondisi alamiah pembelajara. Pembelajar adalah individu yang unikKonstruktivisme sosial memandang setiap pembelajar sebagai individu yang unik dengan keunikan kebutuhan dan latar belakang. Pembelajar juga dipandang secara kompleks dan multidimensional. (Gredler 1997). Konstruktivisme sosial bukan hanya memahami keunikan dan kompleksitas pembelajar, namun juga membangkitkan, memanfaatkan dan memberikan penghargaan pada keduanya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran (Wertsch 1997).b. Pentingnya latar belakang dan budaya pembelajarGredler (1997) juga menekankan pentingnya latar belakang dan budaya pembelajar. Konstruktivisme sosial membangkitkan keberanian pembelajar untuk sampai pada kebenaran versi masing-masing, yang dipengaruhi oleh latar belakangnya, budaya atau lingkungannya. Perkembangan historis atau sistem simbol, seperti bahasa, logika, dan sistem matematika, merupakan faktor bawaan dari pembelajar sebagai anggota dari budaya tertentu dan hal ini dipelajari pembelajar di sepanjang hidupnya. Berbagai simbol tersebut menuntun bagaimana pembelajar belajar dan apa yang dipelajari (Gredler 1997). Hal ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial pembelajar secara alami dengan anggota masyarakat yang berpengetahuan. Tanpa interaksi sosial dengan anggota masyarakat yang berpengetahuan, adalah mustahil untuk memperoleh arti sosial dari sistem simbol yang penting dan belajar bagaimana memanfaatkannya. Anak-anak muda mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi dengan orang dewasa. Dari sudut pandang konstruktivisme sosial, menjadi sangat penting mempertimbangkan latar belakang dan budaya pembelajar sepanjang proses pembelajaran, karena latar belakang semacam ini juga membantu membentuk pengetahuan dan kebenaran yang diciptakan, ditemukan, dan diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung (Gredler 1997; Wertsch 1997).c. Tanggung jawab belajarLebih jauh lagi, ada alasan kuat bahwa tanggung jawab belajar seharusnya berangsur-angsur diberikan kepada pembelajar. Karenanya kostruktivisme sosial menekankan pentingnya keterlibatan aktif pembelajar dalam proses belajar, tidak seperti pandangan dunia pendidikan sebelumnya yang meletakkan tanggung jawab belajar pada guru untuk mengajar sehingga peran pembelajar pasif, bersifat hanya menerima. Von Glasersfeld (1989) menekankan agar pembelajar mengkonstruksi pemahamannya sendiri dan tidak hanya sekedar meniru dan melakukan begitu saja apa yang ia baca. Ketika tiada informasi yang lengkap, pembelajar mencari kebermaknaan dan memiliki kemauan untuk mencoba menemukan keteraturan dan pola kejadian-kejadian di dunia nyata.d. Motivasi belajarAsumsi penting lain mengenai keadaan alami pembelajar berkenaan dengan tingkatan dan sumber motivasi belajar. Menurut Von Glasersfeld (1989) motivasi yang paling cocok untuk belajar secara kuat bergantung pada kepercayaan diri siswa yang ada dalam potensinya untuk belajar. Perasaan akan adanya kompetensi dan kepercayaan akan adanya potensi untuk memecahkan masalah baru, hampir seluruhnya diperoleh dari pengalaman langsungnya (first-hand experience) dalam menuntaskan masalah di masa lalu dan jauh lebih kuat dari pada motivasi dan pemberitahuan eksternal (Prawat dan Floden 1994). Hal ini terkait dengan zone of proximal development nya Vygotsky (Vygotsky 1978) yang berpendapat bahwa sebaiknya pembelajar diberi tantangan yang setingkat, atau sedikit di atas perkembangannya pada saat itu. Berbekal pengalaman sukses sepenuhnya dalam menuntaskan tugas yang menantang, pembelajar memperoleh kepercayaan diri dan motivasi untuk menaklukkan tantangan baru yang lebih besar.2) Peran gurua. Guru (atau instruktur) sebagai fasilitatorMenurut pendekatan konstruktivis sosial, guru harus menyesuaikan perannya dari sebagai instruktur ke peran sebagai fasilitator (Steffe dan Gale 1995). Ketika seorang guru memberikan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran, perannnya sebagai fasilitator membantu pembelajar untuk memperoleh pemahamannya sendiri tentang materi. Selama proses pembelajaran, dalam skenario pembelajaran tradisional pembelajar berperan pasif, dalam pembelajaran konstruktivisme sosial pembelajaran berperan aktif. Dengan demikian, penekanannya berubah dari instruktur dan materi ke pembelajar (Kukla 2000). Perubahan dramatik dalam hal peran ini membawa konsekuensi pada guru untuk memiliki seperangkat keterampilan baru dari sebelumnya sebagai suatu keharusan (Brownstein 2001). Sebagai guru ia memberitahu, sebagai fasilitator ia bertanya; sebagai guru ia ing ngarso, sebagai fasilitator ia tut wuri; seorang guru memberikan jawaban sesuai seperangkat kurikulum, seorang fasilitator, seorang fasilitator memberikan garis besar haluan dan menciptakan lingkungan untuk pembelajar agar bisa menemukan kesimpulannya sendiri; seorang guru cenderung monolog, seorang fasilitator senantiasa dialog dengan pembelajar (Rhodes dan Bellamy 1999). Seorang fasilitator seharusnya juga mampu mengadaptasi pengalaman belajarnya sendiri dalam rangka mengarahkan pengalaman belajar itu menuju ke mana pembelajar ingin menciptakan sendiri nilai yang bermakna.Lingkungan pembelajar seharusnya juga dirancang untuk mendukung dan memberikan tantangan pada proses berpikir pembelajar (Di Vesta, 1987). Meskipun disarankan agar memberikan kepada pembelajar akses untuk menemukan masalahnya sendiri dan proses pemecahannya, seringkali kegiatan ataupun solusinya tidak memadai. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah memberikan pembelajar dukungan untuk menjadi pemikir efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan memainkan peran ganda, yaitu konsultan dan pelatih.3) Kondisi alamiah proses pembelajarana. merupakan proses sosial yang aktifPara pakar konstruktivisme sosial memiliki pandangan belajar sebagai proses aktif di mana pembelajar seharusnya belajar untuk menemukan sendiri prinsip, konsep, dan fakta sehingga sebaiknya diberikan teka-teki yang menantang dan cara berpikir intuitif dar pembelajar (Brown et al.1989; Ackerman 1996; Gredler 1997). Kenyataannya -bagi konstruktivis sosial- prinsip, konsep dan fakta bukanlah sesuatu yang kita bisa temukan begitu saja karena sebelumnya tidak ada dan bukan menjadi prioritas utama bagi masyarakat kita untuk menemukannya. Kukla (2000) berpandangan bahwa prinsip.konsep dan fakta direkonstruksi oleh aktivitas sendiri dan bahwa manusia, yang secara bersama-sama menjadi anggota masyarakat menemukannya untuk menjadi properti dunia nyata mereka.Pakar konstruktivis lain setuju dengan pendapat di atas namun lebih menekankan bahwa individual memberikan makna melalui interaksinya dengan orang lain dan dalam lingkungan tempat ia hidup. Dengan demikian pengetahuan merupakan produk dari manusia yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Ernest 1991; Gredler 1997; Prawat dan Floden 1994). McMahon (1997) setuju bahwa belajar merupakan proses sosial. Ia menambahkan bahwa belajar bukanlah proses yang hanya terjadi di dalam pikiran kita, juga bukan perkembangan pasif dari perilaku kita yang dibentuk oleh kekuatan dari luar diri kita; proses belajar yang berarti terjadi ketika individu terlibat dalam kegiatan sosial.Vygotsky (1978) juga mennyoroti perpaduan dari elemen sosial dan praktikal dalam pembelajaran dengan mengatakan bahwa peristiwa penting dalam proses perkembangan intelektual terjadi ketika berbicara dan aktivitas praktikal, dua jalur perkembangan yang benar-benar independen satu sama lain, menyatu. Melalui kegiatan praktikal seorang anak mengkonstruksi arti pada tingkatan intrapersonal, sedangkan berbicara menghubungkan arti tersebut dengan dunia interpersonal sebagai wahana ia berbagi dengan budayanya.b. Interaksi dinamis antara tugas, guru, dan pembelajarKarakteristik yang lebih jauh dari peran guru sebagai fasilitator dalam sudut pandang konstruktivisme sosial, adalah bahwa guru dan pembelajar memiliki intensitas keterlibatan yang sama (Holt dan Willard-Holt 2000). Hal ini berarti bahwa pengalaman belajar di samping objektif juga subjektif dan membutuhkan kondisi di mana budaya, nilai, dan latar belakang guru menjadi bagian esensial sebagai penghubung antara pembelajar dan tugasnya dalam mengkonstruksi makna. Pembelajar membandingkan kebenaran versinya dengan versi guru dan temannya dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran versi masyarakat yang telah teruji (Kukla 2000). Tugas atau masalahnya adalah adanya interface (batas) antara guru dan pembelajar (McMahon 1997). Hal ini akan memunculkan interaksi dinamis antara tugas, guru dan pembelajar. Hal ini membawa konsekuensi pembelajar dan guru seharusnya mengembangkan suatu kepedulian terhadap sudut pandang orang lain dan kemudian melihat kembali kepercayaan, standar dan nilai-nilainya, dengan demikian berperilaku subjektif sekaligus objektif secara simultan (Savery 1994).Green dan Gredler (2002) menekankan belajar sebagai suatu proses interaktif, meliputi proses yang diskursif (rasional), adaptif, interaktif dan reflektif secara berkualitas. Menurut keduanya fokus utama dari belajar adalah hubungan timbal balik antara guru-siswa. Beberapa penelitian yang lain, juga memberikan alasan pentingnya mentoring (belajar dengan mentor, senior yang berpengalaman) di dalam proses belajar (Archee dan Duin 1995; Brown et al. 1989). Model pembelajaran konstruktivisme sosial dengan demikian menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara siswa dengan guru selama proses pembelajaran berlangsung.Beberapa pendekatan belajar yang sesuai untuk belajar interaktif antara lain pembelajaran reciprocal, kolaborasi kelompok, cognitive apprenticeships, problembased instruction, web quests, anchored instruction dan pendekatan lain yang melibatkan belajar dengan orang lain.4) Kolaborasi di antara pembelajarPembelajar dengan kemampuan dan latar belakang seharusnya berkolaborasi dalam tugas dan diskusi dalam rangka menuju pemahaman bersama tentang kebenaran suatu bidang tertentu. Kebanyakan model konstruktivisme, seperti yang dikemukakan oleh Duffy dan Jonassen (1992), juga menekankan kebutuhan akan kolaborasi antara pembelajar, hal ini jelas berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih mengedepankan sifat kompetitif. Salah seorang penganut Vygotski memberikan catatan bahwa begitu berartinya implikasi dari peer collaboration, sebagai bagian dari the zone of proximal development. Di sini, zone perkembangan proksimal (terdekat) didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual seperti yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara independen dan tingkatan perkembangan potensial seperti yang ditentukan oleh pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan peer lain yang sudah berpengalaman; batasan ini berbeda dengan keadaan biologis alamiah yang fix dari tingkatan perkembangannya Piaget. Melalui suatu proses yang disebut scaffolding (dukungan) seorang pembelajar dapat dapat dipacu mencapai tingkatan di atas keterbatasan kematangan fisik sehingga tidak terjadi proses perkembangan tertinggal di belakang proses pembelajaran (Vygotsky 1978).a) Pentingnya konteksParadigma konstruktivisme sosial memandang konteks dari terjadinya pembelajaran sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri (McMahon 1997). Yang perlu digarisbawahi dari suatu catatan penting bahwa pembelajar merupakan prosesor aktif adalah asumsi bahwa tidak ada satu pun bagian dari seperangkat hukum pembelajaran yang telah digeneralisasi yang dapat diterapkan untuk semua domain (Di Vesta 1987:208). Pengetahuan yang tidak dikontekstualkan tidak mampu memberikan kita keterampilan untuk menerapkan pengetahuan kita dalam tugas-tugas yang autentik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Duffy dan Jonassen (1992), kita bekerja dengan konsep dalam lingkungan yang kompleks melainkan pengalaman dari hubungan timbal balik yang kompleks dari lingkungan yang juga kompleks yang menentukan bagaimana dan kapan suatu konsep digunakan. Salah seorang konstruktivis memberikan catatan bahwa pembelajaran yang autentik atau sesuai situasi adalah pembelajaran di mana siswa mengambil bagian dalam kegiatan yang secara langsung relevan dengan penerapan hasil pembelajaran dan yang terjadi dalam budaya yang sama dengan setting penerapannya (Brown et al. 1989). Cognitive apprenticeship (pelatihan kognitif) dianggap sebagai model konstruktivisme yang efektif dalam pembelajaran di mana model ini mencoba enkulturasi (pembudayaan) siswa dalam kegiatan praktis yang autentik melalui kegiatan dan interaksi sosial dalam cara yang sama dengan pelatihan di bidang keterampilan yang telah terbukti sukses (Ackerman 1996:25). Konteks di mana pembelajaran terjadi maupun konteks sosial di mana pembelajar membawanya ke lingkungan belajar dengan sendirinya menjadi faktor penentu dalam pembelajaran itu sendiri (Gredler 1997).b) Asesmen (penilaian)Holt dan Willard-Holt (2000) menekankan konsep asesmen dinamis, suatu cara mengases potensi sebenarnya dari pembelajar yang secara signifikan berbeda dengan tes konvensional. Kondisi belajar alamiah yang esensial diperluas sampai ke proses asesmen. Bila biasanya asesmen sebagai suatu proses dilakukan oleh seseorang, misalnya guru, di sini dipandang sebagai suatu proses dua arah yang melibatkan interaksi antara guru dan pembelajar. Peranan guru sebagai asesor melakukan dialog dengan siswa yang diases untuk menemukan tingkatan performansnya dalam melakukan tugas pada saat itu dan curah pendapat dengannya tentang cara yang mungkin bisa ditempuh dalam memperbaiki performansnya pada kesempatan berikutnya. Dengan demikian, asesmen dan pembelajaran dipandang sebagai jalinan proses yang tak terpisahkan (Holt dan Willard-Holt 2000).Berdasarkan pandangan ini seorang guru seharusnya memandang asesmen sebagai proses yang terus menerus dalam mengukur pencapaian pembelajar, kualitas pengalamannya dalam pembelajaran dan proses pembelajarannya. Asesmen juga merupakan bagian integral dari pengalaman belajar dan bukan proses yang berdiri sendiri (Gredler 1997). Umpan balik dari proses asesmen berfungsi sebagai masukan langsung yang menjadi dasar untuk perkembangan selanjutnya. Asesmen seharusnya tidak menjadi proses intimidasi yang menyebabkan kecemasan siswa, melainkan proses yang bersifat mendukung yang membangkitkan keberanian siswa untuk ingin dievaluasi di masa mendatang, sehingga harus fokus pada perkembangan yang terjadi pada siswa (Green dan Gredler 2002).5) Pemilihan, cakupan, dan tata urutan materia) Pengetahuan seharusnya ditemukan sebagai keseluruhan terpaduPengetahuan seharusnya tidak dipisahkan ke dalam subjek-subjek yang berbeda (kompartementalisasi), tetapi seharusnya ditemukan sebagai keseluruhan yang terpadu. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya konteks bagaimana pembelajaran dilangsungkan.para tokoh tersebut, pengetahuan seharusnya tidak dikompartementalisasi secara kaku ke dalam subjek atau kategori berbeda namun seharusnya disajikan dan ditemukan sebagai keseluruhan yang terpadu. Alasannya adalah bahwa dunia, tempat yang dibutuhkan oleh pembelajar untuk melakukan kegiatan, tidak bisa didekati dengan bentuk subjek terpisah, melainkan berupa suatu kompleksitas tak terhingga dari fakta, problem, dimensi dan persepsi.b) Keasyikan dan tantangan bagi pembelajarPembelajar seharusnya secara konstan diberi tantangan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan sedikit di atas tingkat ketuntasannya pada saat itu. Hal ini akan menimbulkan motivasi dan membangun lagi keberhasilan sebagaimana yang telah diraih sebelumnya dalam rangka mempertahankan kepercayaan diri pembelajar. Hal ini juga sejalan dengan zone of proximal developmentnya Vygotsky yang dapat dideskripsikan sebagai jarak antara perkembangan tingkat perkembangan aktual (yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara independen) dan tingkatan perkembangan potensial (yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kolaborasi dengan peers yang lebih berpengalaman).Vygotsky lebih jauh mempublikasikan secara luas bahwa suatu pembelajaran dianggap baik ketika pembelajaran tersebut melampaui perkembangan. Kemudian pembelajaran tersebut membangunkan dan membangkitkan keseluruhan perangkat fungsi yang berada di tingkat kematangan untuk hidup di kehidupan nyata, yang terletak di zona perkembangan proksimal. Dengan cara inilah pembelajaran memainkan peranan yang maha penting dalam perlembangan.Dalam rangka untuk sepenuhnya memberikan keasyikan dan tantangan bagi pembelajar, tugas dan lingkungan pembelajaran seharusnya merefleksikan kompleksitas lingkungan sehingga pembelajar seharusnya memiliki fungsi di akhir pembelajaran. Pembelajar seharusnya tidak hanya mendapatkan proses pembelajaran ataupun proses pemecahan masalah, namun juga masalah itu sendiri.Ketika mempertimbangakan tata urutan materi, sudut pandang konstruktivis berpendirian bahwa dasar dari berbagai subjek dapat dibelajarkan pada siapa pun pada tingkatan mana pun dalam banyak bentuk. Hal ini berarti bahwa guru seharusnya pertama sekali memperkenalkan gagasan dasar sehingga menghidupkan dan membentuk banyak topik ataupun area subjek, baru kemudian kembali lagi pada subjek semula dan membangun kembali gagasan tersebut. Prinsip seperti ini secara ekstensif digunakan dalam kurikulum.Juga penting bagi guru untuk relistis, karena meskipun suatu kurikulum kemungkinan dirancang untuk mereka, tak terhidarkan lagi untuk dibentuk ulang oleh mereka menjadi lebih personal yang merefleksikan sistem kepercayaan mereka sendiri, pemikiran dan perasaan mereka terhadap isi pembelajaran maupun pembelajarnya. Dengan demikian, pengalaman belajar menjadi suatu kegiatan yang harus dilakukan bersama. Dengan demikian, emosi dan konteks kehidupan dari yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran harus dianggap sebagai bagian integral dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajar menjadi fokus dalam mempertimbangkan tentang apa yang dipelajari.c) Penstrukturan proses belajarAdalah penting untuk mendapatkan keseimbangan yang benar antara tingkatan struktur dan fleksibilitas yang dibangun dalam proses pembelajaran. Savery menyatakan bahwa semakin lebih terstruktur lingkungan pembelajaran, semakin sulit bagi pembelajar dalam mengkonstruksi arti berdasarkan pemahaman konseptual mereka sendiri. Seorang guru seharusnya menyusun struktur pengalaman belajar sekedar cukup untuk membuat yakin bahwa siswa mendapat arahan yang jelas dan parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran, namun pengalaman belajar seharusnya terbuka dan memberikan peluang yang cukup bagi pembelajar untuk menemukan, menikmati, berinteraksi dan sampai pada kebenarannya sendiri yang telah diverifikasi oleh masyarakat.d) Catatan akhirIntervensi konstruktivisme dalam pembelajaran dengan demikian merupakan intervensi di mana kegiatan kontekstual (tugas-tugas) digunakan untuk menyediakan pembelajar peluang untuk menemukan dan secara kolabortif mengkonstruksi arti sebagaimana yang diungkap dalam intervensi. Pembelajar dihormati sebagai individual yang unik, dan guru lebih cenderung berperan sebagai fasilitator daripada instruktur.4. Paedagogi berdasarkan konstruktivismeKenyataannya, banyak pedagogi yang bergerak di sekitar teori konstruktivisme. Kebanyakan pendekatan yang berkembang dari konstruktivisme menyarankan bahwa belajar yang sempurna menggunakan pendekatan hands-on (keterlibatan personal). Pembelajar belajar melalui eksperimentasi, dan tidak melalui cara pemberitahuan apa yang akan terjadi. Mereka dibiarkan memiliki pendapat sendiri, penemuan, dan kesimpulan. Konstruktivisme juga menekankan bahwa pembelajaran bukanlah suatu proses seluruhnya atau tidak sama sekali melainkan bahwa siswa belajar informasi baru yang disajikan untuk mereka dengan membangun pengetahuan yang telah mereka miliki. Karenanya menjadi penting guru secara konstan mengases pengetahuan yang telah dicapai siswanya untuk meyakinkan bahwa persepsi siswa terhadap pengetahuan baru sama dengan apa yang dimaksudkan guru. Guru akan menemukan bahwa karena siswa membangun pengetahuan yang telah dimiliki, ketika diminta untuk memahami informasi baru, mereka tidak membuat kesalahan. Bisa disebut terjadi kesalahan rekonstruksi apabila kita mengisi kesenjangan antara pemahaman kita dengan pemikiran yang logis namun tidak benar. Guru harus mampu mengidentifikasi dan mencoba membetulkan kesalahan tersebut, meskipun tak pelak lagi bahwa beberapa kesalahan rekonstruksi akan terus terjadi karena faktor bawaan berupa keterbatasan pemahan kita.Pada kebanyakan pedagogi yang berdasarkan konstruktivisme, peran guru bukan hanya mengamati dan mengases namun juga terlibat dalam kegiatan siswa sementara ia juga harus menyelesaikan kegiatannya sendiri, meneriakkan keheranan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menggalakkan cara berpikir logis. (contoh: Saya heran mengapa air tidak meluap keluar melalui bibir gelas yang penuh?) Guru juga melakukan intervensi ketika muncul konflik; namun mereka secara sederhana memfasilitasi resolusi di antara siswa dan regulasi diri, dengan suatu penekanan pada siswa untuk harus mampu menemukan jalan keluarnya sendiri.Sebagai contoh, promosi literasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kebutuhan untuk membaca dan menulis selama aktivitas individual dalam kelas yang penuh tulisan kreatif. Seorang guru, setelah membaca suatu cerita, membangkitkan keberanian siswa untuk menulis dan menulis ceritanya sendiri, atau meminta siswa untuk melakonkan ulang suatu cerita yang telah mereka kenal dengan baik, kedua kegiatan tersebut membangkitkan keberanian siswa untuk membayangkan diri mereka sendiri sebagai pembaca ataupun penulis.Beberapa pendekatan khusus dalam dunia pendidikan yang didasarkan atas konstruktivisme: Konstruktionisme Merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Seymour Papert dan koleganya di MIT di Cambridge, Massachusetts. Papert pernah bekerjasama dengan Piaget institut tersebut di Jenewa. Papert belakangan menyebut pendekatannya constructionism. Pendekatan ini menckup segala sesuatu yang berhubungan dengan konstruktivismenya Piaget, namun bergerak lebih jauh lagi dengan menyertakan bahwa pembelajaran konstruktivisme terjadi dengan baik khususnya ketika siswa mengkonstruksi suatu produk, sesuatu yang eksternal bagi mereka seperti benteng pasir, mesin, program komputer, atau buku. Promotor penggunaan komputer dalam pendidikan memandang suatu kebutuhan yang semakin meningkat untukmengembangkan keterampilan dalam literasi Multimedia dalam rangka mengguanakan peralatan ini dalam pembelajaran konstruktivisme.Pendekatan lainnya: Reciprocal Learning, Procedural Facilitations for Writing, Cognitive Tutors, Cognitively Guided Instruction (suatu program pengembangan profesi dan riset dalam matematika untuk SD yang diciptakan oleh Thomas P. Carpenter, Elizabeth Fennema, dan koleganya di University of Wisconsin-Madison. Premis mayornya adalah guru dapat menggunakan strategi informal siswa (dengan kata lain strategi yang dikontruksi oleh siswa berdasarkan pemahamannya pada situasi kehiduopan sehari-hari, seperti memungut batu kecil dan memetik bunga) sebagai basis utama untuk mengajar matematika di jenjang SD); Anchored Instruction (Bransford et al), Problem dan pendekatan pemecahan solusinya ditanamkan dalam lingkungan naratif), Cognitive Apprenticeship (Collins et al), pembelajaran diperoleh melalui pengintegrasian ke dalam budaya pengetahuan khusus yang implisit dan eksplisit); Cognitive Flexibility (Sprio et al) dan Pragmatic Constructivism.Prinsip belajar dan PembelajaranBelajar adalah proses aktif peserta didik dalam mengkontruksi arti, wacana, dialog,pengalaman fisik. Dalam proses belajar tersebut terjadi proses asimilasi danmenghubungkan pengalaman atau informasi yang sudah dipelajari.Prinsip dalampembelajaran teori kontruktivisme adalah:- Pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting.- Berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat dimanipulasi peserta didik.- Pendidik lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator.- Program pembelajaran dibuat bersama peserta didik.- Strategi pembelajaran,student-centered learning, dilakukan dengan belajaraktif,belajar mandiri, kooperatif dan kolaboratifSecara garis besar, prinsip-prinsip Konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah :1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kemurid, kecuali hanya dengankeaktifan murid sendiri untuk menalar3. Murid aktif megkontruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahankonsep ilmiah4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses kontruksi berjalan lancar5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa6. Struktur pembalajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan7. Mencari dan menilai pendapat siswa8.Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa.E. Implikasi Konstruktivisme dalam PembelajaranAdapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak (Poedjiadi, 1999: 63) adalah sebagai berikut: (1) tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individuatau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, (2) kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memcahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari dan (3) peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitor, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik.Dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivis hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu: a) menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan; b) pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata; c) pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai; d) memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran; e) pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan social peserta didik; f) pembelajaran menggunakan barbagia sarana; g) melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik (Knuth & Cunningham,1996).F. AplikasiTeori Konstruktivismea. Setiap guru akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas dengan jelas-jelasnya namun masih ada sebagian siswa yang belum mengerti ataupun tidak mengerti materi yang diajarkan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat mengajar suatu materi kepada sisiwa dengan baik, namun seluruh atau sebagian siswanya tidak belajar sama sekali. Usaha keras seorang guru dalam mengajar tidak harus diikuti dengan hasil yang baik pada siswanya. Karena, hanya dengan usaha yangkeras para sisiwa sedirilah para siswa akan betul-betul memahami suatu materi yang diajarkan.b.Tugas setiap guru dalam memfasilitasi siswanya, sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para siswa sendirisan bukan ditanamkan oleh guru. Para siswa harus dapat secara aktif mengasimilasikan dan mengakomodasi pengalaman baru kedalam kerangka kognitifnyac. Untuk mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang digunakan para siswa untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dikembangkandan yang dibuat para sisiwa untuk mendukung model-model itu.d. Siswa perlu mengkonstruksi pemahaman yang mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi sehingga guru dalam mengajar bukannya menguliahi, menerangkan atau upaya-upaya sejenis untuk memindahkan pengetahuan pada siswa tetapi menciptakan situasi bagi siswa yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi-konstruksi mental yang diperlukan.e. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadisituasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik.f. Latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari.g. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi engetahuan pada diri peserta didik.G. Kelebihan dan kelemahan teori Konstruktivismea. Kelebihan1. Siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjadi ide dan membuat keputusan.2. Siswa akan lebih mengerti dan boleh mengapliksikannya dalam semua situasi.3. Siswa akan lebih lama ingat suatu konsep4. Siswa dapat berinteraksi dengan baikb. KelemahanKekurangan atau kelemahan dari teori ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya dimana peran guru sebagai pendidik itu sepertinya kurang begitu mendukung.
DAFTAR PUSTAKAAnonim.2012.Konstruktivisme.http://id.wikipedia.org/wiki/Konstruktivisme. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.Anonim.2012.Konsep Belajar Menurut Teori Konstruktivisme. http://contohmakalah. info/konsep-belajar-menurut-teori-konstruktivisme/. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.Prima,Ade.2012.Teori Konstruktivisme.http://ade-prima.blogspot.com/2012/09/teori-konstruktivisme.html. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.Anonim.2012. Teori Pembelajaran Konstruktivisme.http://tugasmahasiswamatematika. blogspot.com/2012/06/teori-pembelajaran-konstruktivisme.html. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.
0