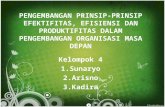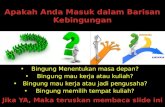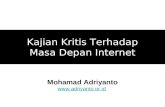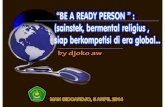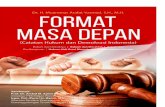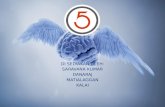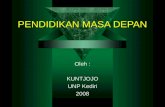Strategi Pertanian Masa Depan
-
Upload
kiki-fatmawati -
Category
Documents
-
view
31 -
download
0
description
Transcript of Strategi Pertanian Masa Depan
EKOLOGI TANAMAN Strategi Pertanian Masa DepanDiajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekologi Tanaman.
Disusun oleh :
Kiki Fatmawati (1137060042)Agroteknologi 4B
JURUSAN AGROTEKNOLOGIFAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATIBANDUNG2015
Pada masa yang akan datang akan ada 3 pola pertanian penting, ialah (1) Pertanian Konvensional; (2) Pertanian Konservasi; (3) Pertanian dengan Teknologi Tinggi.Pertanian konvensional adalah pertanian seperti yang dilakukan oleh sebagian besar petani di seluruh dunia saat ini. Pertanian ini mengandalkan input dari luar sistem pertanian, berupa energi, pupuk, pestisida untuk mendapatkan hasil pertanian yang produktif dan bermutu tinggi. Pada masa yang akan datang sistem pertanian ini akan lebih ramah lingkungan bersamaan dengan lebih banyak input teknologi. Perkembangan atau kemajuan pertanian konvensional pada masa depan dibandingkan masa sekarang terjadi karena peran penelitian bidang ekofisiologi dan pumuliaan tanaman, serta karena tuntutan masyarakat.Pertanian Konservasi juga akan meluas. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai tuntutan terhadap pangan yang bebas pestisida dan bebas dari pupuk kimia, serta kelompok yang ingin agar pertanian tidak mencemari lingkungan. Dua kelompok masyarakat ini akan semakin besar di dunia, demikian pula di Indonesia. Produktivitas sistem ini pada umumnya rendah, mutu fisik atau visual produk juga rendah, tetapi keamanannya tinggi dan dipercaya oleh sebagian konsumen karena nilai zat berkhasiat yang terkadung di dalamnya tinggi. Namun, karena adanya permintaan yang semakin besar dari kelompok-kelompok ini akan mendorong semakin luasnya pertanian konservasi. Pada pertanian konservasi, prinsip utamanya adalah pertanian yang mengandalkan dan berusaha mempertahankan kelestarian alam. Dengan pertanian konservasi diusahakan agar tidak terlalu banyak gangguan ekosistem dalam alam pertanian. Pertanian ini lebih mengandalkan mekanisme ekobiologi dari alam sehingga input yang diberikan pada sistem pertanian ini diusahakan serendah mungkin. Jika diberikan, maka input tersebut berupa bahan-bahan organik alamiah yang bukan hasil budaya. Studi ekofisiologi akan memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kelestarian sistem ini.Pertanian Teknologi Tinggi juga akan meningkat pada masa depan. Pertanian ini akan sangat produktif, produknya bermutu tinggi, aman, kandungan gizi dan zat berkhasiat yang ada di dalamnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Karena itu, pertanian ini memerlukan input tinggi, baik berupa teknologi, bahan-bahan kimia maupun energi. Pertanian ini bisa mengatasi kendala dan hambatan alam, bisa sangat efisien tetapi bisa juga tidak efisien. Pertanian ini juga mungkin tidak menyebabkan degradasi lahan pertanian, maupun alam sekitar karena tidak mengandalkan alam dalam produksi. Pertanian ini lebih mengandalkan teknologi dan input dari hasil budaya. Pertanian ini hanya akan melibatkan pemodal besar, bukan petani.Strategi pengelolaan lahan perlu diubah sesuai dengan masalah yang berkembang saat ini. Suhu udara di bumi memanas, sejak 1861 telah meningkat 0.6oC terutama disebabkan oleh aktifitas manusia yang menambah emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer (IPCC, 2001). IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) (2001) memprediksi bahwa suhu rata-rata global di bumi akan meningkat 1,4 5,8oC pada tahun 2100. Bila upaya pengurangan konsentrasi gas rumah kaca berhasil di tahun 2100, suhu bumi diperkirakan masih akan terus meningkat karena konsentrasi GRK (CO2, CH4 dan N2O) di atmosfer sudah cukup besar dan masa tinggalnya cukup lama, bahkan bisa sampai seratus tahun. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) melaporkan bahwa di Indonesia telah terjadi kenaikan suhu rata-rata tahunan antara 0,2 1,0oC, yang terjadi antara tahun 1970 hingga 2000, sehingga terjadi peningkatan rata-rata curah hujan bulanan sekitar 12-18% dari jumlah hujan sebelumnya. Salah satu upaya untuk mengatasi dan mengurangi perubahan ini dalam sistem pertanian dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:1. Strategi Pengendalian Perubahan IklimBanyak kegiatan baik pelatihan maupun penelitian dari berbagai sektor telah bergeser tidak hanya fokus pada produk dan keuntungan ekonomi saja, melainkan juga mempertimbangkan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang sinergi dengan upaya mitigasi GRK (Gas Rumah Kaca) (Verchot et al., 2007). Adaptasi merupakan cara atau upaya dalam menghadapi efek dari perubahan iklim, dengan melakukan penyesuaian yang tepat dengan melakukan upaya untuk mengurangi pengaruh merugikan dari perubahan iklim, atau memanfaatkan pengaruh positifnya (Nair, 2011).Strategi dan kebijakan umum Kementrian Pertanian (2011) dalam menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura sebagai prioritas utama. Sedangkan mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebab terjadinya perubahan iklim, yaitu dengan menyerap CO2 di udara dan menyimpannya dalam tanaman dan tanah baik dalam ekosistem hutan maupun pertanian dalam jangka waktu yang lama. Berkaitan dengan konsep adaptasi ini, Neudfeldt et al. (2011) menambahkan bahwa usaha pengurangan atau pengalihan resiko dan peningkatan kapasitas untuk mengubah dampak perubahan iklim di masa yang akan datang misalnya pembangunan sarana irigasi, peningkatan diversitas tanaman dan seleksi tanaman tahan kekeringan juga disebut sebagai upaya adaptasi.2. Agroforestri (Perpaduan Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim)Agroforestri merupakan sistem multifungsi lanskap yaitu sebagai sumber pendapatan petani, perlindungan tanah dan air di sekitarnya (Young, 1989), perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengendalian emisi karbon, dan mempertahankan nilai estetika lanskap (Hairiah et al., 2011; Nair 2011). Secara fisik agroforestri mempunyai susunan kanopi tajuk yang berjenjang (kompleks) dengan karakteristik dan kedalaman perakaran yang beragam pula, sehingga agroforestri merupakan teknik yang bisa ditawarkan untuk adaptasi karena mempunyai daya sangga (buffer) terhadap efek perubahan iklim antara lain pengendalian iklim mikro (Van Noordwijk, 2008), mengurangi terjadinya longsor (Hairiah et al., 2011), limpasan permukaan dan erosi serta mengurangi kehilangan hara lewat pencucian (Widianto et al., 2007; Suprayogo et al., 2002), dan mempertahankan biodiversitas flora dan fauna tanah (Dewi 2007). Agroforestri tersusun dari bermacam-macam jenis pohon dan tanaman bawah yang bervariasi umurnya, sehingga sistem ini relatif lebih aman dari resiko gagal panen, dan lebih stabil terhadap goncangan pasar dan akibat perubahan iklim (Budidarsono dan Wijaya, 2004; Van Noordwijk 2008).Agroforestri memberikan tawaran yang cukup menjanjikan untuk mitigasi akumulasi GRK di atmosfer (IPCC, 2001), karena pohon yang ditanam petani pasti bermanfaat secara ekonomi dan kadang-kadang memberikan nilai ekologi. Gas CO2 sebagai salah satu penyusun GRK terbesar di udara diserap pohon dan tumbuhan bawah untuk fotosintesis, dan ditimbunnya sebagai C-organik (karbohidrat) dalam tubuh tanaman (biomasa) dan tanah (bahan organik tanah) dalam waktu yang lama, hingga mencapai 30-50 tahun. Selama tidak ada pembakaran di lahan, emisi gas karbon dioksida (CO2) ke atmosfer dapat ditekan. Di tingkat plot, pohon dalam sistem agroforestri telah banyak dilaporkan bermanfaat dalam mempertahankan kesuburan tanah, mengendalikan limpasan permukaan dan erosi (Widianto et al., 2007; Nair, 2011) dan mengendalikan serangan hama dan penyakit (Schroth et al., 2000). Namun demikian pada kenyataannya tidak semua pohon dapat memberikan dampak yang menguntungkan, tergantung dari pengelolaannya antara lain meliputi pemilihan jenis tanaman dan kombinasinya dengan komponen penyusun lainnya (misalnya ternak), pengaturan sinar yang masuk melalui pengaturan pola tanam dan pemangkasan cabang, dan pemupukan tumbuhan bawah (Hairiah et al., 2011; Budiadi et al., 2012; Lestari et al., 2012), pengaturan kedalaman perakaran tanaman untuk mengurangi kehilangan hara dan meningkatkan efisiensi serapan hara (Rowe et al., 2005; Buresh et al., 2004). Pada skala lanskap agroforestri berfungsi penting dalam tata air, mempertahankan keanekaragaman hayati dan cadangan karbon daratan. 3. Pembangunan Sistem Pertanian-BioindustriSistem Pertanian-Bioindustri merupakan keterpaduan berjenjang Sistem Pertanian Terpadu pada tingkat mikro, Sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat industri atau rantai pasok dan Sistem Agribisnis Terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem Usaha Pertanian Terpadu yang berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti sistem integrasi tanaman-ternakikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas, bioelektrik) atau sistem integrasi usaha pertanian-biorefinery yang termasuk Pertanian Hijau merupakan pilihan sistem pertanian masa depan karena tidak saja meningkatkan nilai tambah dari lahan tetapi juga ramah lingkungan sehingga lebih berkelanjutan. a. Membangun Sistem Pertanian-Bioindustri yang BerkelanjutanSistem Pertanian-Bioindustri yang Berkelanjutan bertumpu pada tiga landasan berimbang, yakni berorientasi pada kesejahteraan sosial petani, pekerja dan masyarakat sekitar, ramah lingkungan dan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani dan pengusaha, dan bukan hanya untuk satu generasi, melainkan juga untuk generasi berikutnya. Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berlangsung di dalam suatu ekosistem, karena itu melestarikan ekosistem melalui penerapan prinsip dan interaksi biologis merupakan bagian dari cara menjamin keberlanjutan dari pembangunan sistem pertanian terpadu itu sendiri.b. Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri yang Menghasilkan Beragam Pangan SehatTujuan utama sistem pertanian-bioindustri adalah untuk menghasilkan pangan sehat, beragam dan cukup. Penyeragaman pola konsumsi pangan dan ketergantungan pada hanya satu atau beberapa pangan pokok tertentu harus dihindari, pola pangan harapan yang berkualitas dan sehat harus terpenuhi dengan sumber pangan yang beragam sesuai keragaman budaya dan potensi daerah. Keragaman pangan harus didukung oleh keanekaraman sumber hayati pangan tinggi, pilihan teknologi tepat guna yang luas, serta kekayaan keragaman produk industri pangan yang sehat sebagai perpaduan kekayaan budaya dan IPTEK.c. Pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri yang Menghasilkan Produk-produk Bernilai TinggiSelain untuk kebutuhan pangan sehat, pertanian-bioindustri ditujukan untuk menghasilkan produk-produk bernilai tinggi. Pilihan prioritas pengembangan produk pertanian-bioindustri dilandasi pertimbangan nilai tambah tertinggi yang dimungkinkan dari proses biorefinery. Orientasi pada pengembangan produk bernilai tambah tinggi akan menciptakan daya saing pertanian-bioindustri yang tinggi. Daya saing dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan memberikan pelayanan yang profesional.d. Membangun Sistem Pertanian-Bioindustri dengan Memanfaatkan Sumberdaya Hayati Pertanian dan Kelautan TropikaLandasan Sistem Pertanian-Bioindustri ialah pemanenan matahari sebagai sumber energi primer dan mengkonversikannya menjadi biomassa melalui proses fotosintesa pada sistem usahatani agroekologi berbasis lahan maupun perairan. Biomassa yang dihasilkan selanjutnya diolah melalui biorefinery, yang dalam hal ini disebut sistem bioindustri menjadi berbagai produk bahan pangan, obat-obatan, pakan, energi, bahan kimia dan berbagai bioproduk lainnya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terletak di daerah tropis memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri. Sistem pertanian Indonesia yang kini masih berorientasi pada produksi dan pemanfaatan sebagian saja dari hasil biomassa dengan mengandalkan input eksternal usahatani yang sangat tinggi harus diubah menjadi berorientasi pada produksi maksimum dan pemanfataan menyeluruh biomassa melalui pemanenan energi matahari atau proses fotosintesa dengan input eksternal seminimum mungkin.e. Membangun Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dengan Menerapkan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maju Saat ini pertanian Indonesia masih berada pada tahap konvensional yakni tahap pembangunan pertanian yang digerakkan oleh kelimpahan faktor produksi yakni sumberdaya alam dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Hal ini dapat dilihat baik dari segi teknologi maupun dari segi struktur produksinya. Dari segi teknologi produksi, peningkatan produksi masih didominasi oleh peningkatan jumlah penggunaan sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik. Sedangkan dari segi struktur produksi akhir, pada umumnya masih menghasilkan produk yang didominasi oleh komoditas primer yang bernilai tambah rendah dan tidak berdaya saing. Sistem pertanian konvensional ini harus sesegera mungkin dimodernisasi, yakni transformasi menuju Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan. Produk-produk pangan yang sehat dan bernilai tinggi dalam jumlah yang cukup dan beragam harus dihasilkan secara berkelanjutan melalui penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan ini didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis bioscience dan bioengineering.
DAFTAR PUSTAKA
BPPP (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Kementrian Pertanian, 2011. Pedoman umum adaptasi perubahan iklim sector pertanian. ISBN 978-602-9462-04-3. 67p.
Buresh R J, Rowe E C, Livesley S J, Cadisch G and Mafongoya P, 2004. Opportunities for capture of deep soil nutrients. In: Van Noordwijk M, Cadisch G and Ong C K (eds.) Below-ground interactions in tropical agroecosystems. Concepts and models with multiple plant components. CABI. p 109-123.
Budiadi, Suryanto P dan Sabarnurdin S, 2012. Pembaharuan paradigm agroforestry Indonesia seiiring meningkatnya isu kerusakan lingkungan dan sustainable livelihood. Dalam: Widiyatno, Prasetyo E, Widyaningsih T S, Kuswantoro D P (Eds.). Proc. Sem. Nas.III. Pembaharuan Agroforestri Indonesia: Benteng terakhir Kelestarian, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Kemakmuran. ISBN: 978-979-16340-3-8. Hal: 168-171.
Budidarsono, S dan Wijaya K, 2004. Praktek konservasi dalam budidaya kopi robusta dan keuntungan petani. Agrivita 26(1): 120-132.
Dewi, W S, 2007. Dampak alih guna lahan hutan menjadi lahan Pertanian: Perubahan diversitas cacing tanah dan fungsinya dalam mempertahankan pori makro tanah. Disertasi. Paska Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
Hairiah K, Ekadinata A, Sari R R dan Rahayu S, 2011. Petunjuk praktis Pengukuran karbon tersimpan di hutan dan lahan-lahan Pertanian berbasis pohon. Ekstrapolasi dari tingkat lahan ke tingkat lanskap. World Agroforestry Centre, ICRAF Southeast Asia.
IPCC, 2001. Climate change 2001: Impacts, adaptation and vulnerability. Report of the working group II. Cambridge University Press, UK, p 967.
Lestari P, Rahayu S dan Widiyatno, 2012. Dinamika penyakit karat tumor pada sengon (Falcataria moluccana) di berbagai pola agroforestri. Dalam: Makalah utama dipresentasikan di Seminar Nasional Agroforestri 3, UB, Malang, 21 Mei 2013. Page 22 Widiyatno, Prasetyo E, Widyaningsih T S, Kuswantoro D P (Eds.). Proc. Sem. Nas.III. Pembaharuan Agroforestri Indonesia: Benteng terakhir Kelestarian, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Kemakmuran. ISBN: 978-979-16340-3-8. Hal: 168-171.
Nair P K R, 2011. Agroforestry systems and environmental quality: Introduction. In: Chang S, Nair V, Kort J and Khasa D (eds.). J. Env. Quality, 40 (3): 784-790.
Neufeldt H, Van de Sand I, Dietz J, Hoang M H, Yatich T, Lasco R, dan Van Noordwijk M, 2011. Climate change, climate variability and adaptation options. In: Van Noordwijk M, Hoang M H, Neufeldt H, Oborn I, Yatich T (eds). How trees and people can co-adapt to climate change. p 1-533.
Rowe E C, Van Noordwijk M, Suprayogo D dan Cadisch, G. 2005. Nitrogen use efficiency of monoculture and hedgerow intercropping in the humid tropics. Plant Soil 268: 61-74.
Schroth G, Krauss U, Gasparotto L, Aguilar A, dan Vohland K, 2000. Pest and diseases in agroforestry systems of the humid tropics. Agroforestry Systems, 50: 199-241.
Suprayogo D, Van Noordwijk M, Hairiah K dan Cadisch G, 2002. The inherent safety-net of ultisols: Measuring and modeling retarded leaching of mineral nitrogen. Eur.J.Soil Sci. 53, 185-194.
Van Noordwijk M, 2008. Agroforestri sebagai solusi mitigasi dan adaptasi pemanasan global: Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan fleksibel terhadap berbagai perubahan. Makalah Bunga Rampai pada Seminar Nasional Agroforestri Pendidikan Agroforestri sebagai strategi menghadapi pemanasan global, UNS, Solo, 4-6 Maret 2008.
Verchot L V, Noordwijk M, Kandji S, Tomich T P, Ong C, Albrecht A, Mackensen J, Bantilan C, Anupama K V, dan Palm C, 2007. Climate change: linking adaptation and mitigation through agroforestry. Mitig Adapt Strat Glob Change, DOI 10.1007/s1 1027-007-9105-6. Springer Sci.
Young A, 1989. Agroforestry for soil conservation. CABI-ICRAF. 276p.