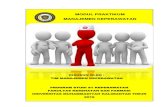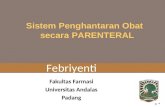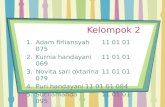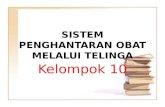Spo
-
Upload
ricco-ardes -
Category
Documents
-
view
80 -
download
10
description
Transcript of Spo
LAPORAN PRAKTIKUMPERTANIAN ORGANIK(AGT 328)
ACARA IBUDIDAYA PADI ORGANIK
Disusun Oleh :
Afit Sidik A1L009189
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS PERTANIANAGROTEKOLOGIPURWOKERTO2012
I. PENDAHULUANA. Latar Belakang
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak.Sistem pertanian organik merupakan sistem produksi holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta mampu pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. Trend pertanian organik di Indonesia, mulai diperkenalkan oleh beberapa petani yang sudah mapan dan memahami keunggulan sistim pertanian organik. Pertanian organik bertujuan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya dan lingkungan, peningkatan nilai tambah ekonomi produk pertanian dan pendapatan petani. Penggunaan pupuk hijau, pupuk hayati, peningkatan biomasa, penyiapan kompos yang diperkaya dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit secara hayati diharapkan mampu memperbaiki kesehatan tanah sehingga hasil tanaman dapat ditingkatkan, tetapi aman dan menyehatkan manusia yang mengkonsumsi (Sutanto, 2002).Pertanian organik mengacu pada bentuk-bentuk pertanian dengan berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada dan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem usahatani, yaitu tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan manusia sehingga saling melengkapi dan memberikan efek sinergi yang paling besar. Pertanian organik memandang alam secara menyeluruh, komponennya saling bergantung dan menghidupi, dan manusia adalah bagian di dalamnya. Prinsip ekologi dalam pertanian organik didasarkan pada hubungan antara organisme dengan alam sekitarnya dan antarorganisme itu sendiri secara seimbang. Pola hubungan antara organisme dan alamnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sekaligus sebagai pedoman atau hukum dasar dalam pengelolaan alam, termasuk pertanian (Anonim, 2009).
B. Tujuan Praktikum
1. Mahasiswa dapat mengetahui teknik budidaya padi organik.2. Mahasiswa dapat mempraktikan teknik budidaya padi organik.
II.METODE PRAKTIKUMA. Alat dan Bahan Alat yang digunakan dalam praktikum budidaya padi organik antara lain cangkul, traktor, sabit, tali, tangki semprot, ember, gelas ukur, meteran, kayu ukuran dan karung.Bahan yang digunakan dalam praktikum budidaya padi organiki adalah benih padi, POC SO-Kontan Lq ( 2 liter), POC So-Kontan Fert (2 liter), Pupuk Kandang 5 ton (jika ada), dan Pestisida nabati maja-gadung dan asap cair
B. Prosedur Kerja1. Persiapan benih a. Rendam benih ke dalam air yang telah dicampur dengan 100 cc POC jenis SO-Kontan Fert selama 24 jam dan sebelum ditiriskan tambahkan segenggam abu sekam + garamb. Lahan yang akan dijadikan persemaian disemprot dengan POC jenis SO-Kontan Lq (konsentrasi 2ml/l), kemudian dibiarkan selama 1 minggu dan usahakan konsisi air macak-macak.c. Tanah dibajak dan langsung digaru, kemudian disemprot dengan SO-Kontan Lq (konsentrasi 2ml/l)d. Dua hari berikutnya benih disebar (umur bibit 18 -21 hari).2. Persiapan Lahana. Lahan sawah sesudah panen jika masih ada jerami dihamparkan tipis secara meratab. Hamparkan irisan tipis/cacahan batang pisang secara merata, jika ada pupuk kandang akan lebih baik ditaburkan secara merata dengan dosis 5 ton/Hac. Semprotkan POC jenis SO-Kontan dengan konsentrasi 4 ml/lt (dosis 70 ml/1000m2)d. Usahakan kondisi air dibuat selalu macak-macak
3. Penanamana. Sistem konvensional diatur dalam baris dan kolom dengan ukuran 20 x 20 Cm atau 23 x 23 Cm b. Sistem legowo 4-1, yaitu setelah 4 baris, kemudian 2 baris kosong. Jarak tanam 20 x 20 cm atau 22 x 22 cm.c. Sistem legowo wayang, yaitu baris dan kolom berukuran 25 x 25 cm dan di antara baris tambahkan 1 (satu) titik rumpun padi. Selain sistem tersebut adapt juga dengan sistem setiap 4 baris tanam, lalu logowo (2 baris tanaman kosong). Jarak tanam 20x20 cm.d. Setiap lubang tanaman terdiri dari 3 batang, umur bibit 18 25 hari.4. Pemupukana. Aplikasikan POC SO-Kontan Lq sekali lagi pada umur 10 hari setelah tanam (hst) melalui tanah.b. Aplikasikan POC SO-Kontan Fert 4 (empat) kali dengan frekuensi 10 hari sejak tanaman umur 25 hst.(sesudah penyiangan pertama) atau pada umur tanaman 25; 35; 45; dan 55 Hst. Konsentrasi yang digunakan 4 ml/lt (dosis 70 ml/1000m2). Setiap aplikasi dilakukan pada pagi hari sekitar jam 10.00 Wib (saat stomata membuka secara optimum). Khusus aplikasi pada umur 45 dan 55 hst tambahkan larutan nira kelapa yang sudah difermentasi dengan hati batang pisang kapok selama 2 minggu sebanyak 5%.5. Pemeliharaana. Pengaturan air dan pengendalian gulma dilakukan seperti biasa. Sebaiknya hindari menggunakan herbisida karena dapat memusnahkan cacing penghembur tanah dan biota tanah yang berguna sebagai pengurai bahan organik tanah.b. Pengendalian hama dan penyakit, sebaiknya dengan menggunakan pestisida nabati seperti maja-gadung, asap cair dll.) yang telah ada atau membuat sendiri, atau menggunakan agensia hayati (seperti jamur Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Trichoderma sp. dan Clyocladium sp.) dan menggalakan pengelolaan habitat. . Aplikasi pestisida nabati dilakukan bersamaan dengan aplikasi pupuk daun SO-Kontan Fert. 6. PemanenanPemanenan dilakukan setelah bulir masak 80%, dan hindari pada saat panen turun hujan.
III. HASIL DAN PEMBAHASANPertanian organik banyak memberikan kontribusi pada perlindungan lingkungan dan masa depan kehidupan manusia. Pertanian organik juga menjamin keberlanjutan bagi agroekosistem dan kehidupan petani sebagai pelaku pertanian. Sumber daya lokal dipergunakan sedemikian rupa sehingga unsur hara, bimassa, dan energi bisa ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah pencemaran (Husnain, 2006).Pertanian organik ada dua macam yaitu (1) Pertanian Organik Murni bila sama sekali tidak dipakai bahan kimia pupuk atau obat-obat hama; (2) Pertanian Semi Organik bila dipergunakan sedikit bahan-bahan kimia baik obat atau pupuk . Sehingga definisi sementara yang muncul adalah suatu teknik pertanian yang menghindarkan penggunaan bahan kimia sintetis , baik dalam bentuk pupuk maupun pestisida , sebagai gantinya dipergunakan bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Pertanian organik dalam pembahasannya tidak jauh dari suatu sistem yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI). System of Rice Intensification (SRI) adalah teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktifitas padi dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara, terbukti telah berhasil meningkatkan produktifitas padi sebesar 50% , bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100%.Metode ini pertama kali ditemukan secara tidak disengaja di Madagaskar antara tahun 1983 -84 oleh Fr. Henri de Laulanie, SJ, seorang Pastor Jesuit asal Prancis yang lebih dari 30 tahun hidup bersama petani-petani di sana. Oleh penemunya, metododologi ini selanjutnya dalam bahasa Prancis dinamakan Ie Systme de Riziculture Intensive disingkat SRI. Dalam bahasa Inggris populer dengan nama System of Rice Intensification disingkat SRI.Metode SRI menghasilkan panen minimal dua kali lipat dibandingkan metode yang biasa dipakai petani. SRI tanaman diperlakukan sebagai organisme hidup sebagaimana mestinya, bukan diperlakukan seperti mesin yang dapat dimanipulasi. Semua unsur potensi dalam tanaman padi dikembangkan dengan cara memberikan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhannya (Kuswara, 2003).
Prinsip-prinsip budidaya padi organik metode SRI1. Tanaman bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai (hss) ketika bibit masih berdaun 2 helai2. Bibit ditanam satu pohon perlubang dengan jarak 30 x 30, 35 x 35 atau lebih jarang3. Pindah tanam harus sesegera mungkin (kurang dari 30 menit) dan harus hati-hati agar akar tidak putus dan ditanam dangkal4. Pemberian air maksimal 2 cm (macak-macak) dan periode tertentu dikeringkan sampai pecah (Irigasi berselang/terputus)5. Penyiangan sejak awal sekitar 10 hari dan diulang 2-3 kali dengan interval 10 hari6. Sedapat mungkin menggunakan pupuk organik (kompos atau pupuk hijau).Keunggulan metode SRI1. Tanaman hemat air, Selama pertumbuhan dari mulai tanam sampai panen memberikan air max 2 cm, paling baik macak-macak sekitar 5 mm dan ada periode pengeringan sampai tanah retak (Irigasi terputus)2. Hemat biaya, hanya butuh benih 5 kg/ha. Tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pindah bibit, tenaga tanam kurang dll.3. Hemat waktu, ditanam bibit muda 5 - 12 hss, dan waktu panen akan lebih awal4. Produksi meningkat, di beberapa tempat mencapai 11 ton/ha5. Ramah lingkungan, tidak menggunaan bahan kimia dan digantikan dengan mempergunakan pupuk organik (kompos, kandang dan Mikro-oragisme Lokal), begitu juga penggunaan pestisida.
Teknik Budidaya Padi Organik metode SRI1. Persiapan benihBenih sebelum disemai diuji dalam larutan air garam. Larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan benih adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut. Kemudian benih telah diuji direndam dalam air biasa selama 24 jam kemudian ditiriskan dan diperam 2 hari, kemudian disemaikan pada media tanah dan pupuk organik (1:1) di dalam wadah segi empat ukuran 20 x 20 cm (pipiti). Selama 7 hari. Setelah umur 7-10 hari benih padi sudah siap ditanam.2. Pengolahan tanahPengolahan tanah Untuk Tanam padi metode SRI tidak berbeda dengan cara pengolahan tanah untuk tanam padi cara konvesional yaitu dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman, terhidar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua minggu sebelum tanam dengan menggunakan traktor tangan, sampai terbentuk struktur lumpur. Permukaan tanah diratakan untuk mempermudah mengontrol dan mengendalikan air.3. Perlakuan pemupukanPemberian pupuk pada SRI diarahkan kepada perbaikan kesehatan tanah dan penambahan unsur hara yang berkurang setelah dilakukan pemanenan. Kebutuhan pupuk organik pertama setelah menggunakan sistem konvensional adalah 10 ton per hektar dan dapat diberikanm sampai 2 musim taman. Setelah kelihatan kondisi tanah membaik maka pupuk organik bias berkurang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemberian pupuk organik dilakukan pada tahap pengolahan tanah kedua agar pupuk bisa menyatu dengan tanah.4. PemeliharaanSistem tanam metode SRI tidak membutuhkan genangan air yang terus menerus, cukup dengan kondisi tanah yang basah. Penggenangan dilakukan hanya untuk mempermudah pemeliharan. Pada prakteknya pengelolaan air pada sistem padi organik dapat dilakukan sebagai berikut; pada umur 1-10 HST tanaman padi digenangi dengan ketinggian air ratarata 1cm, kemudian pada umur 10 hari dilakukan penyiangan. Setelah dilakukan penyiangan tanaman tidak digenangi. Untuk perlakuan yang masih membutuhkan penyiangan berikutnya, maka dua hari menjelang penyiangan tanaman digenang. Pada saat tanaman berbunga, tanaman digenang dan setelah padi matang susu tanaman tidak digenangi kembali sampai panen. Untuk mencegah hama dan penyakit pada SRI tidak digunakan bahan kimia, tetapi dilakukan pencengahan dan apabila terjadi gangguan hama/penyakit digunakan pestisida nabati dan atau digunakan pengendalian secara fisik dan mekanik.Perbedaan sisten tanam padi Organik SRI dengan sistem KonvensionalKomponenSistem konvensionalSistem organic SRI
-kebutuhan benih
-pengujian benih
-umur di persemaian
-Pengolahan tanah
-jumlah tanaman perlubang
-posisi akar waktu tanam
-pengairan
-pemupukan
-penyiangan
-rendemen30-40 kg/ha
tidak dilakukan
20-30 HSS
2-3 kali (Struktur lumpur)
rata-rata 5 pohon
tidak teratur
terus digenangi
mengutamakan pupuk kimia
diarahkan kepada pemberantasan gulma
50-60%5-7 Kg/ha
dilakukan pengujian
7-10 HSS
3 kali (struktur lumpur dan rata)
1 pohon/lubang
posisi akar horizontal (L)
disesuaikan dengan kebutuhan
hanya dengan pupuk organikdiarahkan kepada pengelolaan perakaran
60-70%
Keterangan: HSS = Hari setelah semai.Perbedaan Hasil Cara SRI dengan KonvensionalKebutuhan pupuk organik dan pestisida untuk padi organik metode SRI dapat diperoleh dengan cara mencari dan membuatnya sendiri. Pembuatan kompos sebagai pupuk dilakukan dengan memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan dan sampah rumah tangga dengan menggunakan aktifator MOL (Mikro-organisme Lokal) buatan sendiri, begitu pula dengan pestisida dicari dari tumbuhan behasiat sebagai pengendali hama. Dengan demikian biaya yang keluarkan menjadi lebih efisien dan murah.Penggunaan pupuk organik dari musim pertama ke musim berikutnya cenderung mengalami penurunan rata-rata 25% dari musim sebelumnya. Sedangkan pada metode konvensional pemberian pupuk anorganik dari musim ke musim cenderung meningkat, kondisi ini akan lebih sulit bagi petani konvensional untuk dapat meningkatkan produsi apalagi bila dihadapkan pada kelangkaan pupuk dikala musim tanam tiba.Pemupukan dengan bahan organik dapat memperbaiki kondisi tanah baik fisik, kimia maupun biologi tanah, sehingga pengolahan tanah untuk metode SRI menjadi lebih mudah dan murah, sedangkan pengolahan tanah yang menggunakan pupuk anorganik terus menerus kondisi tanah semakin kehilangan bahan organik dan kondisi tanah semakin berat, mengakibatkan pengolahan semakin sulit dan biaya akan semakin mahal.Dari hasil praktikum padi dengan teknik organik hasilnya lebih tinggi dibandingkan padi dengan system konvensional yang menggunakan pupuk kimia sintetis. Hal ini disebabkan padi konvensional terkena serangan hama wereng yang sangat hebat yag menyebabkab tanaman mati. Gejalanya yaitu tanaman menjadi layu, batang menjadi rapuh dan berwarna coklat. Proses pemeliharaan padi organik dilakukan dengan intensif dan berkala.
IV. KESIMPULAN1. Kegiatan yang dilakukan dalam budidaya padi organik dengan poc antara lain yaitu: pengolahan tanah, pembenihan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT dan panen.2. Teknik budidaya padi organik pada dasarnya sama dengan teknik budidaya padi secara konvensional, hasil yang diperoleh dalam praktikum kali ini lebih baik dengan teknik budidaya padi secara organik.i
LAPORAN TETAPPRAKTIKUM PERTANIAN ORGANIKBUDIDAYA KANGKUNG ORGANIK DENGAN MEDIA TANAM DAN PERLAKUAN BERBEDA
SARAH DWI YUSTIANI05111007112KELAS : AKELOMPOK : 7
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGIFAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS SRIWIJAYAIndralaya 2013I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertanian organik menjadi hal yang saat sedang dikembangkan dengan pesat. Tanah semakin kering, semakin miskin kandungan hara organik yang pada akhirnya merugikan petani dan pertanian saat ini.Atas dasar itulah diperlukan upaya dalam peningkatan kebutuhan bahan organik bagi tanaman. Kompos merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan berupa dedaunan, jerami, kotoran hewan, dan sampah kota. Proses dipercepat melalui bantuan manusia. Secara garis besar membuat kompos berarti merangsang pertumbuhan bakteri (mikroorganisme) untuk menghancurkan atau menguraikan bahan-bahan yang dikomposkan sehingga terurai menjadi senyawa lain. Proses yang terjadi adalah dekomposisi, yaitu menghancurkan ikatan organik molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, mengeluarkan ikatan CO2 dan H2O serta penguraian lanjutan yaitu transformasi ke dalam mineral atau dari ikatan organik menjadi anorganik. Proses penguraian tersebut mengubah unsur hara yang terikat dalam senyawa organik yang sukar larut menjadi senyawa organik yang larut sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan.Karakteristik umum yang dimiliki kompos antara lain : mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah yang bervariasi tergantung bahan asal, menyediakan unsur secara lambat (slow release) dan dalam jumlah terbatas dan mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Kehadiran kompos pada tanah menjadi daya tarik bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitas pada tanah dan, meningkatkan meningkatkan kapasitas tukar kation. Hal yang terpenting adalah kompos justru memperbaiki sifat tanah dan lingkungan, (Dipoyuwono, 2007).Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, dengan cara mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem, keragaman hayati, siklus bologi, dan aktifitas biologi tanah secara alami, sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. sistem pertanian organik menggunakan bahan secara alami atau menghindari penggunaan pestisida, pupuk kimia, atau hormon/zat tumbuh kimia. Oleh karena itu, pertanian organik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pertanian sistem berkelanjutan dengan menerapkan teknologi atau teknik yang menyesuaikan agar ekosistem tetap berjalan seperti apa adanya dan tidak menggangu keseimbangan lingkungan.Petanian Organik adalah sebuah bentuk solusi baru guna menghadapi kebuntuan yang dihadapi petani sehubungan dengan maraknya intervensi barang-barang sintetis atas dunia pertanian sekarang ini. Pertanian organik dapat memberi perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, memperbaiki kualitas hasil pertanian, menjaga pasokan produk pertanian sehingga harganya relatif stabil, serta memiliki orientasi dan memenuhi kebutuhan hidup ke arah permintaan pasar.Bahan organic memiliki peranan penting dalam membentuk kemampuan tanah untuk mendukung tanaman, sehingga jika kadar bahan organic tanah menurun, kemampuan tanah dalam mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Bahan organic adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu system kompleks dan dinamnis yang bersumber dari sisa tanaman dan aau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh factor biologi, fisika, dan kimia.
B. Tujuan
Untuk mengamati dan mengetahui pertumbuhan gulma dan produksi tanaman sayur organik.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Klasifikasi
Kingdom: Plantae (Tumbuhan)Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)Sub Kelas: AsteridaeOrdo: SolanalesFamili: Convolvulaceae (suku kangkung-kangkungan)Genus: IpomoeaSpesies: Ipomoea reptanaKangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Kangkung yang dikenal dengan nama Latin Ipomoea reptans terdiri dari 2 (dua) varietas, yaitu Kangkung Darat yang disebut Kangkung Cina dan Kangkung Air yang tumbuh secara alami di sawah, rawa atau parit-parit (Sujitno, 2004).Kangkung adalah salah satu jenis tanaman sayuran daun yang mampu hidup di darat atau di air. Tanaman kangkung tidak memerlukan persyaratan tempat tumbuh yang sulit. Salah satu syarat yang penting adalah air yang cukup. Apabila kekurangan air pertumbuhannya akan mengalami hambatan. Kangkung diperbanyak dengan stek batang yang panjangnya 20-25 cm atau dengan biji. Untuk penanaman kangkung di darat digunakan benih dari biji, namun dapat pula digunakan stek. Untuk mempercepat perkecambahan diperlukan perendaman benih di dalam air selama satu malam sebelum benih itu disebarkan (Sutarya, 1995).Kangkung tergolong sayur yang sangat populer, karena banyak peminatnya. Kangkung disebut juga Swamp cabbage, Water convovulus, Water spinach. Berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, China Selatan Australia dan bagian negara Afrika (Widiyanto, 1991).Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan - bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003).Di lingkungan alam terbuka, kompos bisa terjadi dengan sendirinya lewat proses alami, rumput, daun-daunan, dan kotoran hewan. Serta sampah lainnya, tetapi untuk menunggu kompos yang berkualitas baik, memerlukan waktu terlalu lama (Murbandono, 1998). Proses pengomposan melalui 3 tahapan dan proses perombakan bahan organik secara alami membutuhkan waktu yang relatif (3-4 bulan), mikroorganisme umumnya berumur pendek. Sel yang mati akan oleh populasi organisme lainnya untuk dijadikan substrat yang lebih cocok dari pada residu tanaman itu sendiri. Secara keseluruhan proses dekomposisi umumnya meliputi spektrum yang luas dari mikroorganisme yang memanfaatkan substrat tersebut, yang dibedakan atas jenis enzim yang dihasilkannya (Saraswati, dkk, 2006). Kompos dikatakan bagus dan siap digunakan jika tingkat kematangannya sempurna. Kompos yang baik dapat dikenali dengan memperhatikan bentuk fisiknya, jika diraba, suhu tumpukan bahan yang dikomposkan sudah dingin, mendekati suhu ruang, tidak mengeluarkan bau busuk, bentuk fisiknya sudah menyerupai tanah yang berwarna hitam. Jika dianalisis dilaboratorium, kompos yang sudah matang akan memiliki ciri yakni, tingkat keasaman (pH) kompos antara 6,5 7,5, memiliki rasio C/N sebesar 10 20, kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, mencapai 110 mek/100 gram, daya absorbsi (penyerapan) air tinggi (Simamora. S, 2006). Kompos diketahui mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kompos mengandung hara makro dan mikro namun secara umum kadarnya rendah bergantung dari jenis bahan organiknya, Oleh karena itu diperlukan sumber hara lain yang berkadar hara tinggi yang dapat meningkatkan kadar hara kompos. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah, merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. lewat proses alamiah. Namun proses tersebut berlangsung lama sekali padahal kebutuhan akan tanah yang subur sudah mendesak. Oleh karenanya proses tersebut perlu dipercepat dengan bantuan manusia. Dengan cara yang baik, proses mempercepat pembuatan kompos berlangsung wajar sehingga bisa diperoleh kompos yang berkualitas baik (Murbandono, 2000).Kangkung (Ipomoea sp.) dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi.. Kangkung merupakan jenis tanaman sayuran daun, termasuk kedalam famili Convolvulaceae. Daun kangkung panjang, berwarna hijau keputih-putihan merupakan sumber vitamin pro vitamin A. Berdasarkan tempat tumbuh, kangkung dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) Kangkung darat, hidup di tempat yang kering atau tegalan, dan 2) Kangkung air, hidup ditempat yang berair dan basah (Syafri, 2010).Pertanian organik dapat memberi perlindungan terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, memperbaiki kualitas hasil pertanian, menjaga pasokan produk pertanian sehingga harganya relatif stabil, serta memiliki orientasi dan memenuhi kebutuhan hidup ke arah permintaan pasar (Syafri, 2010). Hasil penelitian Duong et al. (2006) Bahan orgnik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara tanah juga tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik, biologi dan kimia tanah lainnya. Syarat tanah sebagai media tumbuh dibutuhkan kondisi fisik dan kimia yang baik. Keadaan fisik tanah yang baik apabila dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah, yang semuanya berkaitan dengan peran bahan organik. Peran bahan organic yang paling besar terhadap sifat fisik tanah meliputi : struktur, konsistensi, porositas, daya mengikat air, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan ketahanan terhadap erosi (Suntoro, 2003).III. PELAKSANAAN PRAKTIKUM
A. Waktu dan TempatPraktikum budidaya kangkung organik dengan media tanam dan perlakuan yang berbeda dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 sampai panen, pukul 14.30 WIB. Dilaksanakan di lahan Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
B. Alat dan BahanAdapun alat yang di gunakan untuk praktikum ini adalah 1). Aqua gelas, 2). Cangkul, 3). Garu.Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1) air, 2) benih kangkung, dan 3) pupuk kotoran sapi mentah/ tanpa olah.
C. Cara KerjaAdapun cara kerja dalam praktikum ini sebagai berikut :1. Bagilah lahan yang akan digarap menjadi petakan-petakan. Bersihkan petakan tersebut dari gulma-gulma yang ada lalu gemburkan tanah yang ada di petakan tersebut. Setelah itu, lembabkan tanah tersebut dengan air agar tidak terlalu kering.2. Lalu, campurkan tanah tersebut dengan pupuk kotoran sapi yang telah ditimbang beratnya. Kemudian, aduk pupuk kotoran sapi mentah tersebut dengan rata. Lalu diamkan selama 1 minggu.3. Selah 1 minggu, buatlah jarak tanam untuk menanam kangkung. Selagi buat jarak tanam rendam lah benih kangkung di dalam air. Ini di maksudkan untuk mengambil benih yang baik untuk di tanam.4. Setelah itu, tunggu benih tersebut berkecambah. 5. Setelah satu minggu, lakukan lagi pemupukan ke dua, yaitu dengan menggunakan pupuk kotoran sapi mentah. Dimana pupuk nya di taburkan di sela-sela tanaman kangkung tanpa mengenai daun dari tanaman tersebut.6. Sebelum melakukan proses pemupukan, lakukan lah penyiangan gulma yang tumbuh di petakan tersebut. Ini di maksudkan agar tidak terjadi persaingan dalam menyerap bahan organic yang terdapat dalam pupuk tersebut.7. Lalu, amati dan catat pertumbuhan tanaman kangkung dan pertumbuhan gulma di petakan tersebut. Pengamatan di lakukan 3 hari sekali sampai panen.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Hari/ Tanggal Pengamatan ke-Nama TanamanKeterangan
jumat/15 Maret 20131kangkungS1 : 8 cm
S2 : 11 cm
S3 : 10 cm
S4 : 7 cm
S5 : 7 cm
GulmaBerdaun Lebar : 3 cm
Berdaun Sempit : 6,5 cm
Selasa/ 19 Maret 20132kangkungS1 : 16 cm
S2 : 20,5 cm
S3 : 15,5 cm
S4 : 13 cm
S5 : 18 cm
GulmaBerdaun Lebar : 6 cm
Berdaun Sempit : 9,5 cm
Kamis/ 21 Maret 20133kangkungS1 : 20,5 cm
S2 : 26 cm
S3 : 18 cm
S4 : 17 cm
S5 : 24 cm
GulmaBerdaun Lebar : 10 cmJumlah : 321
Berdaun Sempit : 18 cmJumlah : 256
Senin/ 25 Maret 20134kangkungS1 : 28 cm
S2 : 35 cm
S3 : 26,5 cm
S4 : 25 cm
S5 : 29,5 cm
GulmaBerdaun Lebar : 7 cmJumlah : 396
Berdaun Sempit : 5 cmJumlah : 305
Kamis/28 Maret 20135kangkungS1 : cm
S2 : cm
S3 : cm
S4 : cm
S5 : cm
GulmaBerdaun Lebar : cm
Berdaun Sempit : cm
Senin/ 1 April 20136kangkungS1 : 30 cm
S2 : 40 cm
S3 : 28 cm
S4 : 29 cm
S5 : 32,5 cm
GulmaBerdaun Lebar : 8 cmJumlah : 376
Berdaun Sempit : 10 cmJumlah :209
Keterangan :S1 : sampel tanaman kangkung ke-1S2 : sampel tanaman kangkung ke-2S3 : sampel tanaman kangkung ke-3S4 : sampel tanaman kangkung ke-4S5 : sampel tanaman kangkung ke-5
B. Pembahasan
Dalam praktikum ini dilakakannya penanaman kangkung darat dengan media perlakuan yang berbeda-beda dalam setiap kelompok. Dimana pada kelompok saya mendapatkan perlakuan yang dimana tanaman kangkung di berikan perlakuan pupuk kotoran sapi mentah tanpa olah. Pemberian pupuk kotoran sapi ini di berika dua kali dalam periode penanaman tanaman kangkung darat ini. Pemupukan pertama di lakukan sebelum benih di tanam di petakan yang telah di sediakan. Dimana pemberiank pupuk kotoran sapi mentah ini di lakukan setelah petakan di bersihkan dari guma-gulma yang ada lalu di gemburkan.Setelah di pupuk, tanah tersebut didiamkan selama satu minggu lamanya. Setelah satu minggu baru lah benih tersebut di tanam dengan jarak tanam yang telah di tentukan. Penggunaan jarak tanam ini di maksudkan agar tidak terjadi persaingan dalam memperoleh air dan unsur hara dari tanah. Selain itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung darat dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.Setelah satu minggu penanaman dan benih yang telah di tanam tersebut telah berkecambah dan tumbuh maka di lakukan pembersihan gulma dan setelah itu, dilakukannya lagi pemupukan yang kedua yaitu menggunakan pupuk kotoran sapi mentah atau tanpa olah. Selama pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi, tanaman kangkung darat tersebut mengalami pertumbuhan yang nyata antara satu yang lain. Dilihat dari lima sampel yang diambil dan diamati terjadi pertumbuhan yang sangat signifikat dari satu sampel dengan sampel yang lain. Dimana setiap tiga hari sekali terjadi perubahan pertumbuhan sekitar 2-4 cm.Jika dibandingkan dengan perlakuan kelompok lain, perlakuan kelompok saya lah yang paling subur dan paling banyak perubahan dalam segi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung darat yang kami tanam di lahan yang medianya hanya tanah. Pertumbuahan yang terjadi diperjelas dengan dibandingkan dengan kelompok yang mendapat kan perlakuan yang sama dengan kelompok saya. Dimana tanaman yang mereka tanam tanamannya terjadi pertumbuhan yang hamper sama dengan kelompok saya.Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa tanaman kangkung darat yang diberi perlakuan pupuk kotoran sapi mentah atau tanpa olah lebih subur dan lebih cepat mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan perlakuan yang diberi pupuk biogas dan pupuk kompos atau kotoran sapi matang yang telah mengalami proses.Selain itu, dibandingkan juga dengan media tanamnya, media tanam yang menggunakan tanah lebih subur dibandingkan dengan media tanam yang merupakan pencampuran dari tanah dan pasir. Dilihat dari lapangan bahwa pertumbuhan tanaman kangkung darat pada media tanah dan pasir pertmbuhan nya lebih lambat. Diman tanaman kangkungnya menjadi kerdil.Selain pertumbuhan tanaman kangkung darat yang diamati, pertumbuhan gulma juga menjadi perhatian pengamatan. Dalam hal ini, gulma pada kelompok kami tumbuh juga dengan subur. Dimana terdapat dua jenis gulma yang tumbuh yaitu jenis gulma berdaun lebar dan jenis gulma berdaun sempit seperti teki-tekian. Pertumbuhan gulma yang ada juga ikut signifikat. Ini dikarenakan pengaruh pupuk .Dalam setiap tiga minggu sekali di lakukan lah pengamatan terhadap tanaman yang di tanam di petakan tersebut. Pengamatan ini dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui bagaiman pertumbuhan tanaman kangkung dengan perlakuan yang diberikan yang berbeda-beda setiap petakan.Disaat itu lah terlihat jelas pertumbuhan dari tanaman kangkung yang ditanam. Dimana keadaannya terlihat jelas. Pertumbuhan yang merata terjadi pada tanaman kangkung yang ditanam dengan perlakuan S3 yaitu pupuk kotoran sapi mentah dengan menggunakan media tanah tanpa di campur oleh pasir.Dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman kangkung dengan perlakuan yang lain, tanaman kangkung yang mendapatkan perlakuan S3 tumbuh secara merata tinggi nyadengan subur. Sedangkan tanaman kangkung yang ditanam dengan perlakuan yang lain dan menggunakan media pasir tanaman kangkung terlihat tumbuh dengan kerdil dan kecil. Terlihat sekali ketidak suburban dari tanaman tersebut. Mungkin perbedaab pertumbuhan ini disebabkan oleh kandungan bahan yang terdapat di dalam pupuk yang diberikan dan media yang digunakan.V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan1. Pemberian pupuk kotoran sapi mentah atau tanpa olah memberikan manfaat dalam tanaman kangkung darat.2. Pemberian pupuk membuat tanaman kangkung darat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.3. Tanah yang di beripupuk kotoran sapi mentah mengandung banyak bahan organik yang dapat membuat tanah tersebut menjadi subur.4. Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih.5. Selain tanaman kangkung yang tumbuh dengan subur, gulma juga ikut tumbuh dengan subur.
B. SaranPraktiakan diharapkan dapat mengikuti praktikum ini dengan sungguh-sungguh. Selain itu, praktikan diharapkan mengikuti praktikum ini dengan seksama. Alat dan bahan yang menunjang berjalannya praktikum ini diharapkan disediakan sehingga tidak mengganggu jalannya praktikum.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2004. Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik. SNI 19- 7030- 2004Crawford. J.H. 2003 . Composting of Agricultural Waste in Biotechnology Applications and Research, Paul N, Cheremisinoff and R. P.Ouellette (ed). p. 6877.Isroi. 2008. KOMPOS. Makalah. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, BogorSutanto, R. 2002. Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.Sutarya, R dan G, Grubben, 1995. Pedoman Bertanam Sayuran Dataran Rendah. UGM-Press. YogyakartaSimamora, Suhut & Salundik, 2006. Meningkatkan Kualitas Kompos. Meningkatkan Kualitas Kompos. Kiat Menggatasi Permasalahan Praktis. Agromedia Pustaka.Widiyanto, Eko. 1991. Sinar Tani. Bercocok Tanam Kangkung Darat. Sinar Tani.
IiPertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk produksi yang sehat dengan menghindari penggunaan kimia berbahan aktif dalam hal ini pupuk kimia maupun pestisida kimia untuk menghindari pencemaran udara tanah dan air juga hasil produksi pertanian pada khususnya. selain itu, pertanian organik juga menjaga keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam yang terlibat langsung dalam proses produksi.
Manfaat Sistem Pertanian Organik
Sistem pertanian organik memberikan beberapa manfaaat diantaranya adalah:1. Tanaman menjadi sehat, bebas dari bahan kimia aktif, residu, baik dari akibat oleh pestisida ataupun pemupukan.2. Hasil produksi akan lebih sehat.3. Menjadi pertanian yang mampu menjaga kelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Penerapan Sistem Pertanian Organik
Sistem pertanian organik adalah mengindari penggunaan sarana pertanian yang berbahan kimia aktif, dan mengguanakan sarana pertanian baik pupuk ataupu pestisida dari organik. Secara garis besar penerapan Sistem pertanian organik adalah :
1. Menggunakan bahan organik untuk kesehatan tanaman.2. Tidak menggunakan bahan kimia dalam sarana produksi pertanian
Namun menurut beberapa data yang ada, pertanian diindonesia masih sedikit yang menggunakan pertanian organik, kebanyakan petani masih melakukan sistem pertanian konvensional, ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang sistem pertanian organik. Meskipun pemerintah sudah mulai melaksanakan sistem pertanian berkelanjutan yang tujuannya adalah pertanian organik yang memperhatikan aspek kelestarian alam namun program ini belum sepenuhnya terserap oleh petani indonesia.
Dari segi hasil pertanian indonesia pun demikian, hasil produksi pertanian organik diindonesia masih sedikit dibandingkan dengan hasil yang anorgnik, misalnya dari hasil perkebunan di Indonesia, masih sedikit perkebunan yang menggunakan sistem pertanian organik, sehingga hasil produksinya pun masih sedikit, yang mulai terus berkembang adalah tanaman pangan organik dan hortikultura, meskipun ada beberapa hasil dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang belum tersertifikasi organik, namun dari penerapan sistem pertanian sudah menggunakan sistem pertanian organik yang diharapkan kedepannya meningkatkan kualitas produksi menjadi benar-benar organik dan juga meningkatkan hasil produksi dari segi kuantitas.
Penggunaan Pupuk Organik dan Pestisida Organik
Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem pertanian organik adalah pupuk organik dan pestisida organik (nabati), karena dalam sistem pertanian pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang utama setelah benih. Pengguanaan pupuk organik sangat menentukan arah sistem pertanian kedepannya, menjadi organik atau akan tetep menjadi pertanian konvensional, dalam hal konversi juga penggunaan pupuk organik akan menjadi hal yang perlu diperhatikan, untuk mengembalikan kesuburan tanah volume pupuk organik akan ditambah dengan tujuan untuk menyehatkan tanah dan membebaskan dari unsur residu.
Selain itu, sangat tidak disarankan sekalipun penggunaan pestisida kimia, yang nantinya akan kembali merusak keberlangsungan pertanian organik, disarankan dalam pengendalian hama mengguanakan pestisida nabati atau pestisida organik.
iPERTANIAN ORGANIKPERTANIAN ORGANIK1. Pengertian Pertanian OrganikAda dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertanian organik dalam artian sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan bahan kimia. Mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit sampai perlakuan pascapanen tidak sedikiti pun melibatkan zat kimia, semua harus bahan hayati, alami. Sedangkan pertanian organik dalam arti yang luas, adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan). Dengan tujuan untuk menyediakan produk produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya. Konsep awal pertanian organik yang ideal adalah menggunakan seluruh input yang berasal dari dalam pertanian organik itu sendiri, dan dijaga hanya minimal sekali input dari luar atau sangat dibatasi. (FG Winarno 2002)1. Prinsip Prinsip Pertanian Organik Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian.Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk generasi mendatang.Pertanian organik didasarkan pada:1. Prinsip kesehatan2. Prinsip ekologi3. Prinsip keadilan4. Prinsip perlindunganSetiap prinsip dinyatakan melalui suatu pernyataan disertai dengan penjelasannya. Prinsip prinsip ini harus digunakan secara menyeluruh an dibuat sebagai prinsip prinsip etis yang mengilhami tindakan.1. Prinsip KesehatanPertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan.Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia.Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat.Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di alam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan.Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.1. Prinsip EkologiPertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan.Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam.Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, pembangunan habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.1. Prinsip KeadilanPertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen.Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan ataupun produk lainnya dengan kualitas yang baik.Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya.Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.1. Prinsip PerlindunganPertanian organik harus dikelola secara hati hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Karenanya, teknologi baru dan metode metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung awab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. lmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering). segala keputusan harus mempertimbangkan nilai nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses proses yang transparan dan artisipatif.1. Pengembangan Pertanian OrganikPengembangan pertanian organik harus mengacu kepada prinsip prinsip organik (prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan dan prinsip perlindungan) agar mendapatkan hasil pangan yang bermutu serta aman dikonsumsi. Berdasarkan pertimbangan pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pertanian alternatif:1. Keragaman daur-ulang limbah organik dan pemanfaatannya untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.2. Memadukan sumber daya organik dan anorganik pada sistem pertanian di lahan basah dan lahan kering.3. Mengemangkan sistem pertanian berwawasan konservasi di lahan basah dan lahan kering.4. Memanfaatkan bermacam macam jenis limbah sebagai sumber nutrisi tanaman.5. Reklamasi dan rehabilitasi lahan dengan menerapkan konsep pertanian organik.6. Perubahan dari tanaman semusim menjadi tanaman keras di lahan kering harus dipadukan dengan pengembangan ternak, pengolahan minimum dan pengolahan residu pertanaman.7. Mempromosikan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian untuk memperbaiki citra dan tujuan pertanian organik.8. Memanfaatkan kotoran ternak yang berasal dari unggas, babi, ayam, itik, kambing, dan kelinci sebagai sumber pakan ikan.Sesuai dengan prinsip prinsip pertanian organik, ada sebuah metode pengembangan pertanian yang dikenal sebagai metode bertani tanpa bekerja dikembangkan di Jepang oleh seorang petani Jepang yang berlatar belakang ahli mikrobiologi (mantan seorang ilmuwan laboraturium). Ada empat azas bertani alami yang dipraktikan, yaitu :1. Tanpa pengolahan, yaitu tanpa membajak atau membalik tanah.Tanah sebenarnya mampu mengolah dirinya melalui penetrasi akar akar tumbuhan, aktivitas mikroorganisme, binatang binatang kecil dan cacing cacing tanah.1. Tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan.Kebutuhan pupuk untuk tanaman bisa dipenuhi dengan tanaman penutup tanah semisal leguminose, kacang kacangan dan mengembalikan jerami ladang dengan ditambah sedikit kotoran unggas. Jika tanah dibiarkan pada keadaannya sendiri, tanah akan mampu menjaga kesuburannya secara alami sesuai dengan daur teratur dari tumbuhan dan binatang.Jika tanah dibiarkan secara alami, maka kesuburannya alaminya akan naik. Sisa sisa bahan organik dari tumbuhan dan binatang membusuk, oleh air hujan zat zat hara masuk ke dalam tanah, diserap tanaman dan menjadi makanan mikroorganisme.1. Tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida.Pada dasarnya gulma mempunyai peranan dalam menyeimbangkan komunitas biologi dalam membangun kesuburan tanah. Gulma gulma itu cukup dikendalikan ukan dihilangkan. Mulsa jerami, tanaman penutup tanah, penggenangan air sementara merupakan cara pengendalian gulma yang efektif.1. Tidak tergantung dari bahan bahan kimia.Ketika praktik praktik bertani yang tidak alami dengan pemupukan, pengolahan tanah, pemberantasan gulma maka ketidakseimbangan penyakit dan hama menjadi masalah serius. Hama dan penyakit memang tidak dipungkiri dapat memberi kerugian tetapi masih dalam batas batas yang tidak memerlukan penggunaan zat zat kimia (pestisida). Pendekatan yang arif adalah dengan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit pada sebuah lingkungan yang sehat. Penggunaan bahan kimia hanya efektif untuk sementara waktu, pada saatnya akan menyebabkan terjadinya ledakan hama yang lain karena keseimabangan bioligis terganggu karena penggunaan bahan kimia tersebut.1. Kelemahan dalam Sistem Pertanian OrganikBeberapa hal yang menjadi kelemahan dalam mengembangkan pertanian organik, yaitu :1. Ketersediaan bahan organik terbatas dan takarannya harus banyak2. Transportasi mahal karena bahan bersifat ruah3. Menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa pertanaman dan limbah organik4. Hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non organik yang menggunakan bahan kimia terutama pada awal menerapkan pertanian organik.5. Pengendalian jasad pengganggu secara hayati masih kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia.6. Terbatasnya informasi tentang pertanian organik.1. Kelebihan dalam Sistem PertanianOrganik1. Meningkatan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman.Mikroorganisme seperti rizobium dan mikroriza yang hidup di tanah dan perakaran tanaman sangat membantu tanaman dalam penyediaan dan penyerapan unsur hara. Juga banyak organisme lain yang bersifat menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Misalnya pertumbuhan cendawan akar (Ganoderma sp, Phytopthora sp) dapat ditekan dan dihalangi oleh organisme Trichoderma sp.1. Meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi.Cita rasa hasil tanaman organikmenjadi lebih menarik, misalnya padi organik akan menghasilkan beras yang pulen, umbi umbian terasa lebih empuk dan enak atau buah menjadi manis dan segar. Selain itu pertanian organik juga meningkatkan nilai gizi. Hasil uji laboraturium terhadap beras organik mempunyai kandungan protein, dan lemak lebih tinggi daripada beras nonorganik. Begitu pula nasi yang berasal dari beras organik bisa bertahan (tidak mudah basi) dua kali lebih lama ketimbang nasi dan beras organik. Kalau biasanya nasi akan menjadi basi setelah 12 jam maka nasi dari beras organik bisa bertahan 24 jam. 1. Meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu.Karena dengan penggunaan pupuk organik yang cukup maka unsur unsur hara makro dan mikro terpenuhi semua sehingga tanaman lebih kuat dan sehat untuk menahan serangan beberapa organisme pengganggu dan lebih tahan dari serangan peryakit. 1. Memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur.Buah dan hasil pertanian tidak cepat rusak atau akibat penyimpanan. Buah cabai misalnya akan nampak lebih kilap dengan pertanian organik, hal ini bisa dipahami karena tanaman yang dipupuk organik , secara keseluruhan bagian tanaman akan mendapat suplai unsur hara secara lengkap sehingga bagian bagian sel tanama termasuk sel sel yang menyusun buah sempurna.1. Membantu mengurangi erosi.Pertanian organik dengan pemakaian pupuk organik mejadikan tanah leih gembur dan tidak mudah terkikis aliran air. Struktur tanah menjadi lebih kompak dengan adanya penambahan bahan bahan organik dan lebih tahan menyimpan air dibanding dengan tanah yang tidak dipupuk bahan organik. Pada tanah yang miskin bahan organik, air mudah mengalir dengan membawa tanah
SAINS PETANI SEBAGAI KONTRIBUSI SLPHT UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI
Kasumbogo Untung
PendahuluanPetani merupakan bagian terbesar produsen pangan dan produk-produk pertanian lainnya seharusnya memegang peran dan pelaksana utama pembangunan pertanian di negara Indonesia yang agraris. Setelah kita melaksanakan pembangunan pertanian selama lebih dari setengah abad yang terjadi di lapangan tidak demikian. Petani dan masyarakat pedesaan dalam posisi yang marginal dan memprihatinkan. Petani belum ditempatkan sebagai subyek atau penentu keputusan kegiatan pembangunan pertanian namun tetap sebagai obyek pembangunan pertanian yang secara nasional dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah, bersama dengan segala jajaran dan petugasnya, serta didukung oleh mitra kerja Pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia pendidikan dan penelitian.Banyak jenis program dan proyek pemberdayaan petani telah dilaksanakan oleh Pemerintah, melalui Departemen Pertanian dan departemen-departemen lainnya, namun program-program tersebut masih terpusat pada ketergantungan petani pada Pemerintah. Pola pemberdayaan masih satu arah dengan inisiatif dan pelaksana program adalah Pemerintah dengan para petugas lapangannya. Program pemberdayaan petani kurang bersifat partisipatoris sehingga kurang efektif dalam membebaskan petani dari berbagai bentuk cekaman dan tekanan yang menekan kehidupan mereka. Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu melaksanakan program pelatihan petani PHT melalui kegiatan SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) dengan menerapkan pendekatan partisipatoris dan prinsip petani belajar dari pengalaman telah menghasilkan harapan bahwa petani dapat mandiri, percaya diri dan lebih bermartabat sebagai manusia bebas dalam menentukan nasib dan masa depan mereka. Program pelatihan SLPHT dapat menghasilkan para alumni yang mampu melakukan kegiatan perencanaan dan percobaan untuk memperoleh teknologi budidaya tanaman yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan petani yang spesifik. Makalah ini menguraikan lebih lanjut tentang beberapa latar belakang masalah, prinsip dan sasaran pelaksanaan SLPHT serta pemunculan gagasan Sains Petani oleh para alumni SLPHT. Makalah juga akan membahas bagaimana seharusnya para peneliti dari Universitas menyikapi gagasan Sains Petani. Kebijakan Ketahanan Pangan dengan Pertanian KonvensionalAkar permasalahan yang membawa petani pada kondisi ketergantungan adalah kebijakan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan atau dulu dinamakan program Swa Sembada Beras atau Swa Sembada Pangan. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk yang setiap tahun selalu meningkat seiring dengan laju peningkatan populasi penduduk yang masih secara eksponensial. Keinginan agar bangsa ini dapat berswa sembada beras sudah menjadi program utama Pemerintah Indonesia sejak Kabinet Indonesia yang pertama. Sejak tahun 1970an Pemerintah Presiden Suharto telah menetapkan kebijakan bahwa untuk meningkatkan produksi padi secara cepat hanya dapat dicapai bila para petani padi dapat menerapkan teknologi pertanian modern yang kemudian dikenal sebagai teknologi "revolusi hijau". Teknologi revolusi hijau merupakan teknologi budidaya tanaman padi yang pada waktu itu dimasyarakatkan oleh Pemerintah dengan istilah Panca Usaha Tani (pengolahan tanah, pemupukan dengan pupuk buatan, perbaikan jaringan pengairan, penanaman benih unggul, serta pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida). Kebijakan tersebut pada prinsipnya tetap diikuti oleh Pemerintah periode-periode berikutnya. Setiap tahun Pemerintah selalu menetapkan target produksi padi yang dihasilkan oleh para petani padi. Keberhasilan suatu Kabinet atau Menteri Pertanian dalam mencapai target produksi selalu digunakan sebagai salah satu kriteria keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha membuat banyak kebijakan, program proyek, dan bantuan yang ditujukan pada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi sawahnya. Penerapan teknologi pertanian konvesional dalam program nasional Ketahanan Pangan di Indonesia oleh Pemerintah dibebankan pada puluhan juta petani padi. Pemerintah menyediakan berbagai bentuk fasilitas yang dharapkan dapat digunakan petani sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi sawahnya. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain dalam bentuk penyediaan benih, pupuk kimia, pestisida, sistem jaringan irigasi dan kredit. Program peningkatan produksi pertanian dari Pemerintah yang didukung oleh dunia industri dan para peneliti/pakar/akademisi semakin memojokkan petani (khususnya petani gurem) dalam posisi yang tidak berdaya dalam menentukan masa depannya. Pertanian dengan teknologi revolusi hijau sering disebut sebagai pertanian konvensional, pertanian modern, pertanian industri atau pertanian boros energi. Disebut sebagai pertanian konvensional karena teknologi tersebut sangat umum digunakan di seluruh dunia dan pada kebanyakan komoditi pertanian penting. Pertanian konvensional dinamakan pertanian modern karena pertanian ini memanfaatkan berbagai masukan produksi berupa hasil teknologi modern seperti varietas unggul, pupuk buatan dan pestisida kimia. Hampir semua masukan produksi modern berasal dari luar ekosistem dan bahan bakunya berasal dari bahan bakar fossil sebagai sumberdaya alam tak terbarukan Karena itu sistem pertanian modern sering juga dinamakan sebagai pertanian boros energi. Pertanian konvensional juga dikenal sebagai pertanian industri karena kegiatan produksi pertanian dianggap sebagai kegiatan pabrik yang memproses masukan produksi seperti benih, pupuk, dan yang lain menjadi keluaran yang berupa pangan dan hasil pertanian lainnya serta keuntungan usaha tani. Gliessmann (2007) menyatakan bahwa pendekatan dan praktek pertanian konvensional terutama untuk peningkatan produksi pangan telah diikuti banyak negara baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Menurut Gliessmann, teknologi pertanian konvnsional tersebut bertumpu pada tehnik-tehnik budidaya sebagai berikut:1) Pengolahan Tanah Intensif, 2) Budidaya Monokultur, 3) Aplikasi Berbagai Pupuk Sintetik, 4) Perluasan dan intensifikasi jaringan irigasi, 5) Pengendalian hama, penyakit, gulma dengan pestisida kimia, 6) Manipulasi Genom Tanaman dan Binatang yang menghasilkan varietas-varietas unggul tanaman melalui teknologi pemuliaan tanaman serta rekayasa genetik.Agar pertanian konvensional berhasil meningkatkan produksi sesuai target jangka pendek diperlukan: inovasi teknologi yang cepat, modal besar agar produsen dapat menerapkan teknologi produksi dan pengelolaannya, pertanian skala besar, penanaman varietas unggul secara seragam dalam areal luas dan terus menerus sepanjang musim, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara intensif dan ekstensif, efisiensi penggunaan tenaga kerja tinggi sehingga mengarah pada penggunaan alat dan mesin pertanian, penerapan prinsip-prinsip agrobisnis.Dampak Pertanian KonvensionalDari pengalaman selama berpuluh tahun di semua negara, penerapan pertanian konvensional tidak membawa keadaan yang lebih baik tetapi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Penerapan teknologi pertanian konvensional secara luas dan seragam mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Menurut Gliessmann (2007) dampak samping pertanian konvensional meliputi:1. Degradasi dan Penurunan Kesuburan Tanah.2. Penggunaan Air Berkelebihan dan Kerusakan Sistem Hidrologi.3. Pencemaran Lingkungan berupa kandungan bahan berbahaya di lingkungan dan makanan.4. Ketergantungan petani pada Input-input Eksternal.5. Kehilangan Diversitas Genetik seperti berbagai jenis tanaman dan varietas tanaman pangan lokal/tradisional.6. Peningkatan kesenjangan Global antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang 7. Kehilangan Pengendalian Komunitas Lokal terhadap Produksi PertanianPertanian Konvensional mengakibatkan kerusakan lingkungan serta semakin menghabiskan energi dari sumberdaya alam tidak terbarukan. Harga energi semakin lama semakin meningkat karena persediaan bahan bakar fosil semakin habis. Dilihat dari sisi ekonomi, keuntungan yang diperoleh dari pertanian konvensional semakin menurun. Fenomena pertanian konvensional dengan segala dampak sampingnya tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi sudah dan sedang terjadi di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Kondisi lingkungan dan ekonomi di ekosistem persawahan kita sudah sedemikian kritis sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pertanian secara efektif dan efisien. Berbagai bentuk pemborosan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya sedang terjadi di lahan-lahan sawah dan pedesaan saat ini. Kita akan mewarisi generasi mendatang dengan kerusakan dan biaya lingkungan yang sangat mahal yang sulit untuk dikembalikan lagi. Dengan kesadaran manusia akan lingkungan dan masa depan bumi, praktek Pertanian Konvensional secara bertahap harus diubah dan dikonversikan menjadi Pertanian Berkelanjutan yang bertumpu pada kemampuan, kemandirian dan kreativitas petani dalam mengelola sumberdaya lokal yang mereka miliki. Dukungan politik Pemerintah terhadap konversi pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan harus jelas, tegas dan konsisten agar ekosistem pertanian di Indonesia dapat segera diselamatkan dan dihindarkan dari kerusakan yang lebih parah. Ketidakberdayaan PetaniPenerapan secara luas dan seragam program ketahanan pangan nasional yang bertumpu pada teknologi pertanian konvensional membuat petani dan kelompok tani semakin tidak berdaya, tidak mandiri dan tidak percaya diri. Mereka sangat tergantung pada uluran tangan pihak-pihak lain terutama pemerintah, pengusaha dan peneliti. Dengan ketergantungan tersebut berbagai potensi, aktivitas, kreatifitas dan kearifan petani menjadi tersumbat dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Berbagai kendala yang dihadapi petani yang meliputi kendala internal seperti keterbatasan bibit, air, pupuk, pestisida, modal, pengetahuan dan teknologi serta kendala eksternal seperti akses pasar, penetapan harga, perubahan iklim dan lain-lainnya telah digunakan oleh Pemerintah sebagai alasan melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan petani dalam mengelola lahannya sendiri yang terbatas. Ketergantungan petani pada Pemerintah, pengusaha sarana produksi serta rekomendasi peneliti membuat petani semakin tidak mampu dan tidak berani mengambil keputusan yang terbaik dalam mengelola produksi pertanian yang sesuai dengan keberadaan dan potensi mereka sendiri yang sangat khas lokal. Petani selalu ditempatkan pada posisi yang lemah dalam program pembangunan pertanian yang dirancang dan dilaksanakan Pemerintah yang didukung oleh pengusaha dan peneliti, termasuk peneliti dari Perguruan Tinggi. Bagi Pemerintah petani sampai saat ini masih dianggap sebagai obyek berbagai program dan proyek pembangunan pertanian. Bagi pengusaha petani dianggap sebagai pasar potensial banyak jenis produk-produk industri pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Bagi sebagian peneliti dan akademisi, petani dianggap sebagai obyek kegiatan penelitian serta sebagai pengguna akhir hasil kegiatan atau proyek penelitian yang dilaksanakan atas biaya dari lembaga pemerintah atau swasta sesuai dengan "pesan-pesan" tertentu. Banyak kegiatan penelitian universitas yang kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Persepsi dan orientasi peneliti tentang suatu permasalahan lapangan seringkali berbeda dengan persepsi dan orientasi petani. Di samping banyak topik penelitian para peneliti yang kurang relevan, juga sebagian besar hasil-hasil penelitian tidak sampai pada tangan petani. Pemberdayaan Petani melalui SLPHTProgram/Proyek Pemerintah yang dinilai paling berhasil dalam lebih memberdayakan petani adalah pelatihan petani untuk menerapkan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui program SLPHT (Sekolah Lapangan PHT). Sejak 1989 sampai sekarang lebih dari satu juta petani Indonesia sudah mengikuti program SLPHT yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan dukungan dana APBN, APBD, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Program SLPHT terutama dipusatkan pada pelatihan para petani padi di sentra-sentra beras di beberapa propinsi. Sampai saat ini, SLPHT juga diselenggarakan untuk melatih para petani palawija, sayuran dataran rendah, sayuran dataran tinggi dan perkebunan.Asas-asas SLPHT padi adalah menggunakan sawah selama satu musim tanam sebagai sarana dan tempat belajar utama bagi petani untuk mengelola ekosistem pertanian secara berkelanjutan. Cara belajar lewat pengalaman oleh petani dengan melakukan pengamatan agroekosistem, mengungkapkan dan menganalisis hasil pengamatan, serta menyimpulkan dan menerapkan teknologi dengan metode serta bahan yang praktis dan sesuai dengan kondisi ekosistem dan petani yang khas lokal. Selama satu musim tanam petani bersama kelompoknya belajar sendiri dan memutuskan sendiri teknologi pertanian yang paling tepat yang bisa mereka lakakukan sehingga mereka tidak tergantung pada orang-orang atau pihak-pihak lain. Mengamati, menghitung, mengukur, membandingkan, menganalisis, membuat hipotesis serta mengambil kesimpulan atas dasar penalaran ilmiah, merupakan kegiatan yang mereka lakukan pada setiap hari pertemuan. Bila petani ingin mendalami topik-topik khusus yang ingin mereka ketahui, mereka dilatih melakukan berbagai bentuk pengujian dan percobaan yang mereka rancang dan amati bersama. Hasil pengujian dan percobaan tersebut menghasilkan beberapa teknologi yang menurut keyakinan mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Topik-topik khusus meliputi berbagai masalah pengelolaan ekosistem termasuk budidaya tanaman, pengelolaan tanah dan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman sampai masalah pengolahan dan pemasaran hasil (Untung, 2007). Setelah petani menyelesaikan satu periode SLPHT (disebut "alumni" SLPHT) banyak pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan coba-coba yang mereka peroleh di SLPHT kemudian diterapkan dan dilanjutkan di lahan sawahnya masing-masing. Dalam menerapkan berbagai prinsip dan teknologi PHT para petani alumni SLPHT selalu melaksanakannya secara terpadu, holistik dan berkelompok dalam kelompok taninya masing-masing. Hasil positif yang dirasakan petani setelah melalui pengalaman bertahun-tahun, para alumni SLPHT merasa semakin mampu menyelesaikan berbagai permasalahannya selama ini secara mandiri. Sejak penyelenggaraan SLPHT, banyak konsep dan teknologi yang ditemukan sendiri oleh petani alumni SLPHT di banyak propinsi dan pada banyak komoditi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan). Beberapa teknologi kreasi petani dapat menghasilkan keluaran yang secara ekologi dan ekonomi lebih baik daripada teknologi hasil para peneliti dan lembaga-lembaga penelitian, termasuk peneliti Universitas. Berbeda dengan temuan para peneliti maka hasil temuan petani dengan cepat dan luas diseminasikan pada para petani di tingkat lokal, daerah, nasional dan bahkan sampai tingkat global. Kelihatannya proses diseminasi hasil percobaan ke pengguna akhir lebih cepat dan efektif melalui jaringan komunikasi petani daripada melalui prosedur birokrasi pemerintah. Hasil-hasil dan perolehan tersebut membuat petani lebih percaya diri dan ingin disejajarkan dengan kelompok peneliti profesional yang bekerja di lembaga-lembaga penelitian pertanian dan universitas. Konsep Sains PetaniDari pengalaman-pengalaman tersebut di atas kelompok petani alumni SLPHT memunculkan istilah Sains Petani yang mungkin saya artikan sebagai suatu sains yang dikembangkan dengan prinsip: " dari, oleh dan untuk petani". Petani alumni SLPHT menyadari bahwa penyelesaian permasalahan lapangan yang dinamis tidak dapat dilakukan dengan mengikuti kebiasaan orang tua atau orang sekitarnya tetapi harus dapat dibuktikan dengan penalaran ilmiah. Caranya adalah dengan melakukan percobaan, pengkajian, pengamatan, analisis dan pengambilan kesimpulan tentang penyelesaian masalah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan petani setempat. Kegiatan-kegiatan percobaan dan pengkajian tersebut dilaksanakan sendiri oleh petani dan kelompok tani. Bila dipandang perlu dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk peneliti dari universitas. Petani sudah memiliki modal untuk mengembangkan dan menerapkan Sains Petani yang berupa intuisi, pengalaman, pengetahuan dan budaya baru dalam mengelola secara bijaksana dan berkelanjutan segala sumberdaya yang mereka miliki, termasuk sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber dana yang terbatas.Konsep Sains Petani perlu ditanggapi oleh komunitas peneliti di lembaga-lembaga penelitian dan uniiversitas secara positif dan kreatif. Meskipun dalam pihak lain gagasan Sains Petani dapat dianggap sebagai tantangan dan kritik bagi pemerintah, universitas dan para peneliti agar mereka meninjau kembali kebijakan, strategi dan program yang menempatkan petani pada posisi lemah, yaitu di bawah posisi Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Universitas. Kita harus menempatkan petani pada posisi yang sejajar sebagai mitra kerja Pemerintah, lembaga Penelitian dan Universitas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian. Petani memerlukan pengakuan, dukungan serta kerjasama yang positif untuk mengembangkan Sains Petani sehingga petani secara mandiri mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas temuan, kearifan dan teknologi petani yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya setempat yang beranekaragam. Diharapkan bahwa dengan kerjasama antara "petani peneliti" dengan para peneliti universitas dapat memperkaya dan memajukan khazanah ilmu pengetahuan kita. Kesimpulan 1. Program Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran produksi pangan jangka pendek semakin memojokkan petani pada posisi lemah, terpinggirkan serta tidak berdaya.2. Petani tidak mampu secara mandiri mengambil keputusan mengenai pengelolaan lahan sawahnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.3. Penerapan teknologi pertanian konvensional termasuk untuk peningkatan produksi pangan mengakibatkan dampak samping negatif bagi lingkungan, sosial budaya serta secara ekonomi semakin tidak efektif dan efisien.4. Pelatihan SLPHT mampu mengubah petani alumni SLPHT dari budaya pasif tidak berdaya menjadi budaya aktif, kreatif, inovatif dan berwawasan ilmiah.5. Sains Petani sebagai suatu ilmu yang dikembangkan dengan prinsip "dari, oleh dan untuk" petani merupakan pernyataan kemandirian dan kemampuan petani sekaligus sebagai koreksi bagi komunitas peneliti pertanian yang masih mempertahankan kesenjangan komunikasi dengan petani.6. Konsep Sains Petani perlu ditanggapi secara positif dan kreatif oleh para peneliti, yaitu dengan menerapkan kemitraan kerja sejajar dengan para petani.
Daftar Pustaka
Gliessman, S.R. 2007. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food System. Second Edition. CRC Press. New York.Untung, K. 2007. Kebijakan Perlindungan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKAAnonim, 2009. semangatbelajar.com. Pertanian Organik Teknologi Ramah Lingkungan. Diakses tanggal 3 Juli 2011.Husnain dan H. Syahbuddin. 2006. Mungkinkah pertanian organic di Indonesia peluang dan tantangan. htpp://io.ppi-jepang.org/article. Diakses tanggal 1 Juli 2011.Kuswara dan Alik Sutaryat, 2003. Dasar Gagasan dan Praktek Tanam Padi Metode SRI (System of Rice Intencification). Kelompok Studi Petani (KSP). CiamisNingsih, F, 2007. Prospek pertanian organic di Indonesia. Bisnis organic. Jakarta.Reijntjes, S.J., D. Andow, M.A. Altieri. 1999. Pertanian masa depan, Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah. Kanisius. Yogyakarta.SNI 01-8729-2002. Standar Nasional Indonesia. Sistem Pangan Organik. Badan Standarisasi Nasional.Sutanto, R. 2002. Pertanian Organik Menuju Pertanian Alternatf dan Berkelanjutan. Kanisius. Yogyakarta.