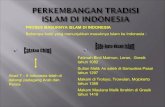Sejarah tradisi pesantren
-
Upload
didiksantoso-iaii -
Category
Documents
-
view
30 -
download
5
Transcript of Sejarah tradisi pesantren
1. SEJARAH TRADISI PESANTREN Oleh: Zamakhsyari Dhofier,* PENDAHULUAN Jumlah lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia pada kurun waktu 20 tahun terakhir, berkembang sangat cepat; pada bulan Desember 2007 yang lalu telah mencapai sebanyak 17.5061 . Dalam buku Tradisi Pesantren yang saya tulis tahun 1980 dan telah diterbitkan ulang 7 kali oleh LP3ES2 , menguraikan perkembangan jumlah lembaga pesantren di pulau Jawa dari tahun 1831 sampai dengan tahun 1977. Berdasarkan laporan Departemen Agama, jumlah lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia pada tahun 1987 sebanyak 6.5793 ; dan pada tahun 1990 belum terjadi perkembangan jumlah yang cukup berarti. Lonjakan jumlah lembaga pesantren yang luar biasa terjadi mulai tahun 1990 sebagai buah dari kebijakan baru Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bulan Maret 1989 memberikan legalitas yang sama dengan sekolah- sekolah negeri tingkat dasar dan menengah terhadap madrasah-madrasah tingkat dasar dan menengah yang dikembangkan di pesantren. Disamping itu, mulai tahun tersebut, banyak sekali generasi muda yang berlatar-belakang pendidikan pesantren berhasil menyelesaikan pendidikan guru di berbagai perguruan tinggi. Lonjakan yang spektakuler selama 17 tahun tersebut, saya perkirakan akan terus berlanjut. Pada tahun 2020 mendatang jumlah lembaga pesantren kemungkinan akan mencapai sekitar 25.000. Jumlah lembaga pesantren yang terus berlanjut tersebut disebabkan karena lembaga pendidikan pesantren inilah yang dengan cepat dapat memberikan santunan pendidikan bagi generasi muda pedesaan yang memerlukan pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Departemen Pendidikan Nasional yang mengutamakan standar kualitas sulit menambah jumlah fasilitas pendidikan menengah dan tinggi yang mencukupi kebutuhan serta biaya yang terjangkau peserta didik di pedesaan. LATAR BELAKANG SEJARAH Pesantren mempunyai latar-belakang sejarah yang sangat panjang yang tidak dapat dipahami dari sudut perkembangan jumlah lembaganya. Meskipun demikian, ada baiknya saya memulai uraian sejarah pesantren dengan mengkaji data paling awal yang tersedia, yaitu laporan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tahun 18314 tentang lembaga-lembaga pendidikan penduduk Jawa yang mencatat jumlah lembaga-lembaga pengajian Al-Quran dan pesantren sebanyak 1.853. Van der Chijs, seorang pejabat pendidikan Belanda yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1831 untuk merancang bantuan lembaga-lembaga pengajian dan pesantren di Jawa mengembangkan pendidikan model Eropa, mengemukakan bahwa sejumlah besar * Rektor Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, Lulusan Australian National University, Penulis Buku Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. 1 Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Desember 2007, hal 127 dan 132 mencatat jumlah pesantren di seluruh Indonesia mencapai 17.506 dan santri sebanyak 3.289.141. 2 Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Cet. Ketujuh, 1997, LP3ES, Jakarta 3 Lihat Zamakhsyari Dhofier, Tradition & Change in Indonesia Islamic Education, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 1995, hal. 123. 4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, op.cit., hal. 35 2. lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengajarkan tidak lebih dari pembacaan Quran, dan hanya sebagian kecil murid diajar menulis Arab. Van der Chijs berpendapat lembaga-lembaga semacam itu tidak layak untuk mengembangkan pendidikan moderen model Eropa; yang layak hanyalan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja. Laporan Pemerintah Hindia Belanda tahun 18855 mencatat perkembangan jumlah lembaga pengajian dan pesantren di seluruh Jawa (kecuali Kesultanan Yogyakarta) mencapai 14.929, dengan murid sebanyak 222.663. Menurut van den Berg, yang lebih paham tentang kualitas pendidikan pesantren memberikan pandangan yang lebih baik dari pada van der Chijs, dan berpendapat bahwa 4/5 dari lembaga tersebut memberikan pengajaran dasar pembacaan Quran; sekitar 3.000 lembaga mengajarkan pengetahuan dasar bahasa Arab dan kitab-kitab pelajaran agama Islam tingkat dasar, antara lain kitab Safinah al-Najah, Sullam al-Tauhid, dan Sharah al-Sittin. Van den Berg juga menilai bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pesantren mencapai sebanyak 300 buah. Lulusannya banyak yang berhasil melanjutkan pendidikannya di Makkah, Saudi Arabia, dan setelah kembali ke Indonesia menjadi pendidik-pendidik yang sangat berpengaruh, bahkan melakukan pembaharuan pemikiran keislaman di masyarakat Indonesia. Lonjakan jumlah lembaga pengajian dan pesantren dari 1.853 buah pada tahun 1831 menjadi 14.929 dengan jumlah santri mencapai 222.663 pada tahun 1885 adalah buah dari pesatnya perkembangan hubungan laut antara negeri Belanda dan jajahannya, Hindia Belanda. Dengan ditemukannya kapal api menjelang abad ke-19 dan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, perusahaan kapal Belanda KPM diberi izin oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengangkut jemaah haji Indonesia. Belanda juga mencabut resolusi-resolusi tahun 1825, 1831 dan ordonansi tahun 1859 yang melarang umat Islam Indonesia melakukan perjalanan haji ke Makkah. Kesempatan melakukan ibadah haji tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam Indonesia. Pada tahun 1887, sebagaimana dituturkan oleh Bernard Dahm, di 43.000 desa di Indonesia sudah terdaftar sebanyak 48.819 haji dan 21.500 guru dan kyai pimpinan pesantren. Sejak tahun 1890, di Indonesia setiap tahun bertambah sekitar 10.000 haji. Itulah sebabnya Pemerintah Kolonial mulai ketakutan terhadap aktivitas masyarakat pesantren6 . Snouck Hurgronje yang melakukan penelitian di Makkah selama 6 bulan pada tahun 1881 untuk bahan penulisan disertasi doktornya menjelaskan bahwa pada tahun tersebut di Makkah terdapat tidak kurang dari 5.000 mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Makkah7 . Menyadari semakin kuatnya kesadaran Pan Islamisme masyarakat pesantren sebagai buah pergaulan mereka selama di Makkah, Snouck yang diangkat sebagai penasehat Pemerintah Kolonial pada tahun 1890, menyarankan Gubernur Jendral di Batavia agar memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat elit pribumi untuk memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda sebagai bagian dari upaya membatasi pengaruh pesantren dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik masyarakat pribumi8 . Survai yang dilakukan oleh kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa 1942-1945) tahun 1942 mencatat jumlah pesantren serta 5 Ibid, hal. 35 6 Bernard Dahm, History of Indonesia in the Twentieth Century, London: Pall Mall Press, hal. 10 7 Snouck Hurgronje, Mecca in the Later Part of the Nineteenth Century, Leiden: E.J. Brill, 1931, hal. 1931 8 Harry J. Benda, The Crecent and the Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation of Java, W. Van Hoeve, Ltd., The Hague, 1958, hal. 57. 3. madrasah sebanyak 1.871, dan murid-muridnya sebanyak 139.4159 . Penurunan jumlah pesantren dan madrasah tersebut pada masa pendudukan Jepang dibandingkan dengan hasil survai tahun 1885, merupakan buah dari upaya Pemerintah Hindia Belanda membatasi perkembangan jumlah pesantren dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah bagi murid-murid Indonesia, dan mulai pertengahan dasawarsa 1910-an memberikan kesempatan yang lulus sekolah atas mengikuti pendidikan tinggi. Jumlah seluruhnya sebanyak sekitar 100.00010 , hampir sama dengan jumlah berkurangnya santri dari tahun 1885. Kedua, dengan berkecamuknya Perang Dunia I dan II serta bergantinya kekuasaan pemerintahan Syarif Husein di Saudi Arabia ke pemerintahan Ibnu Saud, jumlah santri senior dari Indonesia yang belajar ke Masjidil Haram di Makkah mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga lembaga pesantren dan madrasah kekurangan guru. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan baru Indonesia yang merdeka, masyarakat dan pemerintah mengutamakan pengembangan sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi moderen. Pesantren mengalami stagnasi. Baru pada awal tahun 2001, pemerintah menyadari potensi pesantren untuk menyantuni kebutuhan pendidikan bagi generasi muda pedesaan dan pinggiran kota. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang maju hanya dapat dikembangkan di kota-kota besar dan hanya dapat menyantuni kebutuhan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi. Sejak tahun 2001 tersebut, pemerintah mengembangkan Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pesantren, setelah menyadari betapa cepatnya perkembangan pesantren di wilayah-wilayah pedesaan, sehingga pada Desember 2007 jumlahnya telah mencapai 17.509. PESANTREN PADA MASA JAYANYA Untuk dapat menatap ke masa depan dengan penuh percaya diri, maka makalah ini akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama: seberapa besarkah peran para ulama di nusantara pada masa jayanya (1400-1680) sehingga mereka mampu meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta intelektualisme Islam yang tangguh. Periode masa jaya ini perlu dibagi kedalam dua periode mendaki puncak kejayaan (1400-1511), dan periode turun dari puncak ke dataran (1511-1680). Periode 1400-1511 merupakan periode pesta pora rempah-rempah dan perdagangan di Asia Tenggara, khususnya di wilayah nusantara. Puncak kejayaan itu tergambar pada besarnya kapal-kapal jung milik para pedagang di nusantara yang mendominasi perdagangan selama abad ke-15. Jung terbesar yang pernah ada adalah sebuah pengangkut militer berbobot mati kira-kira 1.000 ton, dibuat di Jepara untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513. Sebagai pusat perdagangan paling ramai di Asia Tenggara dan juga sebagai pusat penyebaran Islam sebelum direbut oleh Portugis pada tahun 1511, Malaka berkembang sebagai kota kosmopolitan yang paling mendunia, bahkan bila diukur dari sudut jumlah bahasa yang dipakai oleh para pedagang di kota itu, yaitu sekitar 35 bahasa. Para ulama yang mendampingi para pedagang Muslim yang memegang dominasi aktivitas perdagangan di nusantara memusatkan kegiatannya pada pembangunan komunitas Muslim (masa formative period masyarakat 9 Ibid, hal. 40. 10 Lihat H.J. Benda, op.cit, hal. 31. 4. Muslim). Formative Period itu meliputi banyak hal, bukan hanya dalam bidang keagamaan saja. Salah satu aspek yang juga sama pentingnya ialah proses pembentukan kebudayaan Melayu Modern dimana bahasa Arab menjadi acuan utama bagi pemilihan kata-kata serta tulisan Arab Melayu yang disebut huruf Jawi. Dominasi bahasa Melayu sebagai lingua franca aktivitas perdagangan serta kehidupan politik di wilayah Nusantara jelas sekali dari perubahan sistem pemerintahan dari Hindu Buddhis menjadi kesultanan. Naskah-naskah dalam bahasa Melayu Jawi yang paling tua ditemukan pada akhir abad ke-16, dan penulisnya adalah Hamzah Fansuri. Para ulama dan pemikir 400 tahun sebelumnya mungkin disibukkan oleh aktivitas dakwah dan pembimbingan umat yang baru terbentuk. Periode 1511-1680 menghadapi ancaman Portugis, dan pada abad ke-17 ancaman baru yang jauh lebih kuat dari Belanda dan Inggris. Pada awal periode ini Portugis mendominasi peperangan laut yang memaksa pedagang nusantara menggunakan perahu kecil-kecil pengangkut lada agar dapat lari lebih cepat menghindari patroli Portugis. Dan untuk menghindari kontrol Portugis di lautan Hindia para pedagang Muslim di nusantara membangun jalur alternatif Islam ke Laut Merah, berlayar dari Aceh langsung melintasi Samudra Hindia lewat Maladewa menuju Mesir. Itulah sebabnya Kesultanan Aceh menjadi makmur, terutama di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1638). Khawatir atas ancaman asing yang membahayakan eksistensi komunitas keagamaan Islam yang baru akan mulai mapan, sejumlah ulama menulis karya-karya yang diperlukan untuk menjadi pegangan yang lebih kuat, agar umat Islam (terutama ulama dan pemikir) lebih dapat mendalami ajaran dan intelektualisme Islam melalui bacaan. Kedua, makalah ini juga ingin menjelaskan bagaimana para ulama mampu berperan sebagai pembangun dan pengembang bahasa dan sastra Melayu, dan ketiga, bagaimana mereka mampu mengembangkan moral keislaman dalam masyarakat, dan menuntun para pemimpin menjalankan roda pemerintahan dengan moral keislaman, dari sistem kerajaan Hindu-Budis menjadi sistem kesultanan. Pada masa kejayaan pesantren antara tahun 1400 sampai dengan 1680 tersebut pesantren melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan hebat antara lain, Hamzah Fansuri, Syamsuddin al- Sumatrani, Arraniri, dan al-Singkili. Tokoh-tokoh tersebut adalah ulama besar, intelektual, pemikir dan pembentuk peradaban Melayu klas dunia yang juga pelaku sejarah dalam pentas politik dan pemerintahan. Ada seorang alim lagi yang lahir di Pasei yang setelah saya kaji dengan serius, sangat penting untuk dimasukkan sebagai pemikir dan alim agung, meskipun belum ditemukan peninggalan-peninggalannya dalam karya-karya tulisan, namun jasa-jasanya diketahui dengan jelas sebagaimana dicatat oleh para pelaku serta pencatat sejarah nusantara; namanya Syekh Nurullah. Dari catatan sejarah itulah diketahui bahwa jasa Syekh Nurullah sangat spektakuler mungkin melebihi jasa empat tokoh yang lahir sesudahnya. Kelima pemikir besar tersebut, hanya Arraniri yang lahir di luar Aceh. Syekh Nurullah lahir sekitar tahun 1490 dan meninggal pada tahun 1570 dalam kedudukan sebagai Sultan Cirebon. Hamzah Fansuri lahir di Barus (1550?-1604?). Syamsuddin lahir di Pasei dan meninggal tahun 1620. Arraniri lahir di Ranir, Gujarat, pada dasawarsa 1590an dan meninggal tahun 1658, dan al-Singkili lahir di Singkel, meninggal tahun 1693. 5. Pada periode antara tahun 1490-1690 itu, kelimanya mampu meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmu keislaman di nusantara. Oleh karena itu, untuk dapat memahami rumit dan kedalaman kreativitas pemikiran mereka, terlebih dahulu perlu diketahui perkembangan situasi ekonomi, politik, agama, dan kultural Asia Tenggara antara tahun 1400-1690. Mereka berlima adalah pemikir besar dan sekaligus pelaku sejarah dalam peradaban Islam sebagai peradaban dunia yang masih memainkan peran sangat penting pada periode tersebut. Disamping itu, mereka berlima hidup di wilayah nusantara, wilayah yang sangat penting dan menjadi panggung baru dalam percaturan peradaban dunia. Sepertinya, setelah emporium Abbasiyah berakhir oleh serbuan Hulaghu Khan pada tahun 1258, serta kemunduran perdagangan Muslim di wilayah Timur Tengah dan Lautan Tengah, masyarakat nusantara pada periode 1258-1511 dapat bertindak sebagai salah satu penyelamat Dunia Islam yang mulai melemah pemornya. Penyelamat lainnya: Kesultanan Turki, Kesultan Mughal dan Dinasti Mamluk di kawasan Mesir, Syam, Hijaz, dan Nubia. Sultan Salim di Palestina memang menang dalam Perang Salib; tetapi dalam format percaturan peradaban antara Asia dan Eropa, pengalaman Perang Salib menguatkan upaya para pemikir dan pemimpin Eropa untuk dapat mengalahkan Islam. Islam telah menguasai percaturan dalam peradaban dunia selama sekitar 1.000 tahun, yaitu sejak zaman Khulafaur-Rasyidin sampai dengan kegagalan Turki menduduki kota Wina pada tahun 1611. Cita-cita Eropa mengungguli Islam, mulai terwujud setelah Umayyad terusir dari Cordoba pada tahun 1498, dan sejak tahun itu Eropa terus melaju melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia. Kajian ini berarti searah dengan kajian Prof. Muhammad Sayed Naquib al-Attas yang melakukan periodisasi peradaban dan sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia moderen bukan kelanjutan dengan sejarah benua India, melainkan merupakan kelanjutan dari sejarah peradaban Islam dan Eropa. Dengan pudarnya Majapahit, bahkan Kepulauan Melayu sepertinya melepaskan diri dari keterpakuannya dengan peradaban India. Bahasa Melayu dan Jawa kuno melepaskan diri keterikatannya dari bahasa Sansekerta; demikian pula abjad dan aksara yang berakar kepada tulisan Sansekerta berubah sepenuhnya ke abjad dan tulisan Arab pegon atau Arab Jawi. Buku-buku karya Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Arraniri, dan Abdurrauf al-Singkili itulah yang melegitimasi bahasa dan sastra Melayu Islam yang ditulis dengan huruf Arab Jawi. Adalah suatu keajaiban, Arraniri yang berdarah asli Arab dan lahir di Ranir, Gujarat, menulis hampir seluruh karya-karyanya dalam bahasa Melayu moderen dan dalam huruf dan abjad Arab Jawi. Selama sekitar 150 tahun pada periode sejak meninggalnya Gajah Mada 1358-1511, masyarakat nusantara menjadi pelaku yang penting dalam percaturan dan akulturasi peradaban dunia. Pertama, memudarnya Majapahit setelah meninggalnya Gajah Mada, tidak menjadikan kehidupan politik dan ekonomi nusantara memudar. Perdagagan rempah-rempah dengan Gujarat justru berkembang pesat. Eropa Barat semakin memerlukan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh karena mereka semakin kaya setelah berhasil merebut kendali perdagangan internasional di Eropa Selatan dan Barat serta Lautan Tengah dari tangan para pedagang Muslim. Kedua, munculnya Kerajaan Malaka pada tahun 1403, yang kemudian berkembang sebagai emporium baru yang kuat setelah menjelma sebagai sebuah kesultanan Muslim mulai tahun 1407, selama satu abad Kesultanan Malaka mampu mengembangkan wilayahnya sebagai 6. transito perdagangan Muslim yang makmur, serta sebagai pusat penyebaran dan studi Islam, serta pusat penyebaran bahasa dan sastra Melayu, yang menurut al-Attas berakar dari Melayu Barus dan Pasei, bukan Melayu Riau. Sejumlah ulama Hadramaut dan Gujarat melakukan eksodus ke wilayah nusantara. Kemakmuran Malaka meluas ke seluruh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, dan wilayah nusantara berkembang sebagai produsen rempah-rempah terbesar yang paling makmur. Hal ini berakibat terjadinya perubahan kehidupan keagamaan semua kelompok masyarakat nusantara secara revolusioner. Pada abad ke-16 ini industri perkapalan di Asia Tenggara maju pesat. Kelemahan Hinduisme sebagai bagian emporium Majapahit yang memudar diganti oleh menguatnya Islam sebagai agama baru penduduk nusantara yang memadukan dan meramukan trilogi keislaman, perdagangan dan ke-Melayuan dalam satu etika dan logika peradaban. Ketiga, kemakmuran pedagang nusantara menurun pada abad ke-16 meskipun sampai dengan tahun 1640 masih mampu bertahan sebagai produsen rempah-rempah. Penurunan kemakmuran pedagang nusantara itu disebabkan karena Portugis merebut Malaka pada tahun 1511 dan kemudian Maluku oleh Portugis, yang mengakibatkan para pedagang nusantara (terutama pedagang Jawa yang selama abad ke-15 memegang ekspansi perdagangan yang paling kuat) kehilangan dominasinya, dan hanya sebagai pemasok. Kapal-kapal jung Jawa dirampas oleh Portugis setelah serangan Dipati Unus terhadap Malaka dipatahkan pada tahun 1513, dan sebagian lagi dihancurkan. Yang tersisa adalah kapal-kapal kecil yang menghubungkan kota-kota pedalaman dan kota-kota pantai pemasok. Para pedagang nusantara kehilangan kemampuan mereka dalam perdagangan interinsuler dan internasional. Dominasi peradaban Islam dalam pentas Asia Tenggara berangsur-angsur menurun digantikan oleh menguatnya peradaban Eropah. Islam di Cordoba terusir dari daratan Spanyol. Kesultanan Mughal juga semakin melemah. Pada posisi dan lingkungan ekonomi-politik seperti inilah para pemikir besar di wilayah Kesultanan Aceh, yang pada kurun waktu antara 1590 sampai dengan tahun 1638, masih mampu bertahan sebagai kesultanan dengan perdagangan yang cukup makmur, berupaya merumuskan dasar-dasar intelektualisme Islam, yang waktu itu menghadapi tekanan berat oleh ancaman peradaban Eropa Barat. Intelektualisme Islam yang dirumuskan oleh para ulama pendahulu tersebut merupakan hasil ijtihad yang nilai dan kedalaman kreativitasnya sangat tinggi, dan tangguh meskipun para ulama pewaris masa-masa berikutnya menghadapi tempaan badai kolonialisme Eropa Barat selama kurang lebih 350 tahun. Islam di nusantara yang diwariskan oleh para ulama itu, diakui oleh Prof. Muhammad Naquib al-Attas sebagai Islam yang universal yang akan tetap kuat menghadapi perkembangan semua zaman, yaitu Islam yang mampu membentuk karakter masyarakat Islam sebagai ummatan wasathon yang tasammuh dan mampu menjadikannya sebagai khoira ummah. Islam warisan para ulama itu, dan tumbuh terus (meskipun menghadapi badai kolonialisme Eropa yang mengakibatkan tertinggal dengan kemajuan peradaban Eropa), serta mampu memperkuat dimensi kerohanian umat. Islam di nusantara itu terbukti tumbuh sebagai agamanya suatu bangsa di negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia yang ingin terus maju dan oleh karena itu diharapkan mampu memberikan makna hidup yang lebih tinggi bagi peradaban kemanusiaan dewasa ini. Keunggulan Islam di nusantara ini semua berkat dari unggulnya kualitas dasar-dasar intelektualisme Islam, sebagaimana ditulis sendiri oleh 7. Arraniri: saya pengikut Syafiiyyah dalam masalah fiqh, pengikut Asyariyyah dalam masalah aqaid, dan pengikut Juneidiyyah dalam masalah Tasauf. Keyakinannya itu ditanamkan oleh ulama pewaris pada setiap awal tulisannya di berbagai kitab, yang juga diikuti oleh para ulama penerus yang ingin membuktikan bahwa ulama penerus tersebut mampu merawat, menjaga dan mengembangkannya. Kolonialisme Eropa Barat selama 350 tahun itu memang menyebabkan intelektu-alisme Islam di nusantara terhambat perkembangannya, karena harus pindah ke desa-desa. Kolonialisme Eropa menguasai kota-kota dan seluruh pantai nusantara. Pusat-pusat studi Islam yang berbobot yang mampu mewisuda mahasiswa sekualitas Syekh Nurullah, Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Arraniri, dan Abdurrauf al-Singkili memang hancur di perkotaan karena dihantam oleh badai kolonialisme. Lahan desa memang tidak cukup subur untuk mengembangkan intelektualisme Islam yang tinggi mutunya, tidak pula cukup pupuk (yaitu dalam bentuk komunikasi intelektual dengan para ulama di Timur Tengah dan pusat-pusat studi Islam di Gujarat) yang dapat diimpor, dan tidak cukup pula tenaga ahli yang berkualitas untuk meningkatkan mutu intelektualisme Islam di nusantara. Pusat-pusat studi Islam di luar negeri pun pada waktu itu sedang sangat merana. Namun demikian, Islam di nusantara tetap kuat dan berkembang, meskipun untuk sementara melakukan kontemplasi di desa-desa dalam kelompok- kelompok Tasauf dan tarekat. Dan buahnya jelas, pesantren-pesantren dan madrasah sampai kini tetap kuat dan berkembang dengan jumlah dan jaringan pendidikan Islam yang paling luas dari pada negeri-negeri Muslim lainnya. MENATAP KE MASA DEPAN Fajar harapan baru mulai terbuka pada awal abad ke-20. Sebagian kecil generasi muda ahli waris ulama memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi modern selama beberapa dasawarsa pada abad ke-20. Kelompok cendekiawan baru yang terbentuk ini selama tujuh dasawarsa pertama abad ke-20 masih terpukau oleh kemilaunya peradaban Barat yang melemahkan kesadaran mereka untuk dapat menghargai warisan tradisi dan sejarah kebudayaan bangsanya sendiri. Warisan dan jasa para ulama-pun dilupakan, bahkan dianggap sebagai penyebab kegagalan nenek moyang mengatasi dominasi penjajah. Sebagian diantara mereka itu kecewa dan menilai warisan pemikiran Islam para ulama masa lalu telah usang dan menjadi penyebab pengekang dinamika umat. Mereka mempertentangkan antara tradisi dengan modernitas. Antara tahun 1924 dan 1955 sejumlah pemimpin Islam bahkan saling bertengkar, dan saling mengkafirkan karena salah menafsirkan masalah-masalah tradisi dan modernitas. Beruntunglah, mulai seperempat terakhir abad ke-20 muncul tokoh-tokoh yang mendalami karya-karya para ulama terdahulu dan menyadari tingginya nilai peninggalan para ulama tersebut. Prof. Dr. Sayed Muhammad Naquib al-Attas, misalnya, telah menulis buku bejudul: The Mysticism of Hamzah Fansuri yang diterbitkan oleh University of Malay Press tahun 1970. Tahun 1972, ia menerbitkan lagi sebuah buku: Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan sejumlah tulisan lainnya yang mengupas sumbangan besar Hamzah 8. Fansuri, Syamsuddin al-Sumatani, Arraniri dan Abdurrauf al-Singkili dalam pengembangan bahasa, sastra, kebudayaan serta penulisan sejarah Melayu. Selama 400 tahun karya-karya ulama yang juga sarjana-sarjana tangguh, terabaikan dan tertimbun oleh debu pengabaian tanpa ada perhatian dari para pemikir Islam. Dalam buku-bukunya itu al-Attas mengungkapkan kekagumannya terhadap Hamzah Fansuri sebagai seorang penyair dan Sufi Melayu yang paling masyhur. Hamzah Fansuri memberikan bukti kehebatan para ulama seangkatannya dan ulama yang mendidiknya dalam bentuk tulisan-tulisan. Buku-bukunya itu dimaksudkan untuk memantapkan dasar-dasar pemikiran serta kerohanian Islam dalam bentuk tulisan-tulisan berbahasa Melayu, agar masyarakat yang tidak menguasai bahasa Arab dapat mempelajari ilmu pengetahuan melalui tulisan. Dengan demikian, pengetahuan yang diperolehnya dapat lebih mantap dan selalu dapat dicek melalui tulisan. Tulisan-tulisan Hamzah Fansuri tersebut berawal dari tahun 1590an. Karya-karya Hamzah Fansuri itu pulalah yang membakukan bahasa dan sastra Melayu yang Islami yang ditulis dengan Arab Pegon atau lebih dikenal Tulisan Arab Jawi. Dengan demikian, bahasa dan sastra Melayu menjadi mapan dan dapat berkembang hidup, lengkap dalam bentuk tulisan yang memungkinkan ulama generasi berikutnya dapat mendalami dan meneruskan bahasa dan kebudayaan Melayu. Arraniri yang lahir di Ranir, Gujarat, tidak mungkin dapat menjadi mahasiswa dalam bidang kebudayaan, bahasa dan sastra Melayu dan muncul sebagai ulama dan sarjana Melayu bila tidak belajar dari karya-karya Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani dan karya-karya Melayu lain yang ditulis oleh ulama dan sarjana lainnya, baik sebelum generasinya Hamzah Fansuri maupun yang seangkatannya. Sebagaimana akan disinggung nanti, dalam penulisan khusus untuk buku-buku Tasaufnya, Arraniri mengutip sebagai rujukannya tidak kurang dari 69 buku-buku yang telah terbit. Mungkinkah para penulis pendahulu Arraniri tersebut hanya gemar membaca dan tidak mau menulis? Demikian pula guru-gurunya Hamzah Fansuri, mungkinkah mereka hanya membaca buku-buku yang telah terbit dan mengajarkannya kepada Hamzah Fansuri secara lisan tanpa mengajarnya menulis? Langkah Hamzah Fansuri itu diikuti oleh murid-muridnya dan para ulama berikutnya sehingga sastra Islam Melayu segera dapat berkembang pesat dan mencapai puncaknya berupa karya-karya Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin Arraniri, dan Abdurrauf as- Singkili pada akhir abad ke-17. Keempat ulama tersebut sangat penting untuk diakui sebagai peletak pertama dasar-dasar pemikiran dan kerohanian Tasauf di nusantara dalam bentuk tulisan. Tentu saja para ulama pendahulu yang membesarkan dan memperkaya karya-karya empat ulama tersebut perlu pula diakui jasa-jasanya. Hamzah, Syamsuddin, Arraniri dan Abdurrauf memahami, menguasai dan dapat menulis karya-karya keislaman dalam bahasa Melayu karena belajar dari guru-guru dan ulama pendahulunya. Dari kelima ulama, sarjana dan budayawan agung itulah generasi sekarang seharusnya mengetahui bahwa keempat ulama tersebut menimba ilmu dari para ulama yang sejak abad ke-11 berkumpul dan membangun jaringan keulamaan di Barus. Dari penggalian arkeologi para ilmuwan bulan Oktober 1999 diketahui bahwa beberapa ratus tahun sebelum Hamzah, Syamsuddin, Arraniri, dan Abdurrauf, para ulama di Barus dan Pasei telah mampu menguasai ilmu keislaman serta mampu membangun dan mengembangkan bahasa dan sastra Melayu Islam 9. yang menjadi inti dari Kebudayaan Melayu. Dengan demikian, akar-akar keulamaan pada dasarnya telah berkembang dan terjalin sejak abad ke-11 di Barus, dan kemudian berkembang setelah berdirinya kesultanan Pasei pada akhir abad ke-13. Jumlah dan jaringan ulama meningkat pesat sejak Malaka menjadi transito perdagangan Muslim yang sangat ramai mulai tahun 1407; dan kemudian berkembang menuju puncak kejayaan setelah Tun Perak, ipar Sultan Muzaffar Syah diangkat sebagai perdana menteri dan melebarkan sayap kekuasaannya di berbagai wilayah Semenanjung Malaka dan pantai-pantai timur pulau Sumatra. Perlu diketahui bahwa Malaka dapat menjadi pusat transito perdagangan Muslim dan pusat studi Islam yang paling ramai, kuat dan masyhur juga berkat jasa Pasei. Parameswara, seorang pangeran dan menantu Hayam Wuruk yang lari dari Majapahit pada tahun 1402 mendirikan kerajaan Malaka pada tahun 1403. Pada tahun 1407, saat usianya sudah mencapai 72 tahun, Parameswara menikah dengan putri Sultan Pasei. Dapat dipastikan bahwa, atas pertimbangan mertuanya, Parameswara boleh menikahi putrinya asal ia memeluk agama Islam. Parameswara setuju memeluk agama Islam dan ia menjadikan Malaka sebagai pusat transito perdagangan Muslim dengan gelar Sultan Megat Iskandar Syah. Sultan Muzaffar Syah, putra Sultan Megat Iskandar Syah dari istri seorang pedagang kaya-raya dari Pasei, muncul sebagai seorang Sultan yang kuat yang memerintah Malaka mulai tahun 1446 dan menjadikan Malaka berkembang sebagai emporium yang mampu menandingi Siam, menganeksasi Pahang, Pasei, Trengganu, Patani, Kampar, Indragiri, Kedah, Johore, Jambi, Bengkalis, dan Kepulauan Carimon. Keberhasilannya membangun emporium Malaka itu atas jasa perdana menterinya, Tun Perak, ipar Sultan Muzaffar Syah. Dengan meninggalnya Tun Perak pada tahun 1488, Malaka mulai meredup sinarnya, dan pada tahun 1511 direbut oleh Portugis. Sejak tahun 1511 tersebut, para pedagang Muslim di wilayah nusantara mulai mengalami kemunduran. Kesultanan Pasei- pun berada dibawah pengaruh Portugis. Pada sekitar tahun 1520, di ujung utara pulau Sumatra muncul seorang kuat baru, Sultan Ali Mughayat Syah, yang berhasil mengembangkan Kesultanan Aceh dan pada bulan Mei 1521 dapat mengalahkan armada Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Brito di laut lepas, dan berturut-turut menyatukan Deli, Daya, Pidir dan Pasei pada tahun 1424. Sayang, Kesultanan Aceh gagal merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1537 dan kegagalan itu diikuti oleh meninggalnya Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1539. Persaingan internal terlalu berkepanjangan sehingga Kesultanan Aceh baru menguat kembali pada waktu Sultan Iskandar Muda naik tahta pada tahun 1607. Beliau mampu menjadikan Kesultanan Aceh yang makmur dan jaya sampai wafatnya pada tahun 1636. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun kolonialisme Eropa Barat menguasai percaturan politik di Asia Tenggara, Kesultanan Aceh mampu bertahan sebagai satu-satunya kesulta-nan di nusantara yang terbebas dari penjajahan Belanda sampai tahun 1873. Namun karena percaturan perdagangan internasional, kekuatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai sepenuhnya oleh Inggris, Belanda, dan Perancis, Kesultanan Aceh sulit untuk dapat mengembangkan kekuatan umat Islam dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Yang menarik sekali ialah, pada periode antara tahun 1570-1630, yang oleh Prof. Anthony Reid, penulis South-East Asia in the Age of Commerce digambarkannya sebagai 10. periode Islamisasi paling kuat di nusantara, Islam dideklarasikan oleh penguasa sebagai agama resmi di berbagai kesultanan, antara lain: Mataram (di Jawa Tengah dengan gelar Sultan Agung Sayyidin Panatagama), Sulawesi Selatan (1603-1612), Buton, Lombok, Sumbawa, Mindanao dan Kalimantan Selatan. Disamping itu para penguasa kesultanan-kesultanan yang sudah lama mapan, Aceh, Johor, Patani, Banten, dan Ternate mengembangkan kekuasaannya ke daerah pedalamannya masing-masing sejalan dengan tuntutan agar penduduknya memeluk agama Islam. Saya yakin, ini semua karena buah yang ditanamkan oleh para ulama angkatan Hamzah Fansuri dan para ulama sebelumnya serta para ulama generasi berikutnya Hamzah lahir di Barus (diperkirakan pada tahun 1550). Karya-karya prosanya dalam bahasa Melayu adalah Asrar al-Arifin fi bayan Ilm al-Suluk wat-Tauhid, Syarab al-Asyikin, dan Al-Muntahi, sedangkan karya-karya puisinya adalah Syair Jawi fi Bayan Ilm al-Suluk wat- Tauhid, Syair Perahu, dan Syair Dagang. Seorang muridnya yang juga sangat terkenal, adalah Syamsuddin al-Sumatrani, menulis paling tidak empat buku: Kitab al-Harakah, Mirah al- Muminin, Dzikr Dairah Qaba Qawsayni aw Adna, dan Mirah al-Muhaqqiqin. Karier politik Syamsuddin sangat tinggi. Ia diangkat sebagai Syaikhul Islam Kesultanan Aceh dan juga memegang jabatan diplomatik karena mengatur urusan dan kegiatan luar negeri Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah Aceh tahun 1589-1604 adalah murid Samsuddin dalam masalah keislaman dan masalah-masalah kebudayaan. Hal ini berarti bahwa Syamsuddin bukan sekedar menguasai ilmu fiqh, Tasauf, ilmu Aqaid, tetapi juga sarjana kebudayaan dan ahli strategi dalam diplomasi dan ilmu pengetahuan politik internasional. Setelah mendalami dasar-dasar intelektualisme Islam yang tertuang dalam buku-buku karya Nuruddin Arraniri, al-Attas menyimpulkan bahwa Arraniri kemungkinan memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada Hamzah Fansuri dalam pengemba-ngan kehidupan intellektualisme dan kerohanian umat Islam di nusantara. Arraniri seorang alim dan penulis yang sangat produktif. Buku-bukunya yang terbit dalam bidang tauhid, Tasauf, fiqh, hadis, sejarah, dan bidang-bidang studi keislaman yang lain dalam bahasa Melayu antara tahun 1634 dan 1644 berjumlah tidak kurang dari 19 buah. Beberapa buku tersebut disusun atas perintah Sultan Iskandar Tsani dan Sultanah Safiyyat al-Din Syah. Bukunya yang berjudul Bustan al- Salatin fi Dzikri al-Awwalin wa al-Akhirin terdiri dari 7 jilid yang dimaksudkan sebagai karya ensiklopedia, untuk dijadikan patokan serta standar pemahaman berbagai ajaran Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu. Antara tahun kembalinya ke Ranir sampai meninggalnya pada tahun 1658, Arraniri menulis lagi 3 buah buku dalam bahasa Arab berjudul: 1. Al-Lamaan bi takfir man qala bi khalq al-Quran, 2. Sawarim al-Siddiq li qati al-Zindiq, 3. Rahiq al-Muhammadiyyah fi tariq al-Sufiyyah. Sebagian besar merupakan terjemahan kedalam bahasa Arab dari tulisan-tulisannya dalam bahasa Melayu di Aceh. Dapat dilihat bahwa Arraniri hanya produktif dalam menulis pada waktu berada di Aceh, dan hampir semuanya dalam bahasa Melayu yang berarti Arraniri memiliki kecintaan dan keterikatan kepada peradaban Melayu lebih kuat daripada dengan komunitas Arab dan komunitas Muslim di Ranir. Sayang Arraniri tidak menyebutkan tentang penguasaannya terhadap kebudayaan dan bahasa Melayu dan buku-buku yang dibacanya yang berkaitan tentang Islam, kebudayaan dan bahasa Melayu. 11. Sebagai seorang alim keturunan Arab dan lahir di Ranir, Gujarat, Arraniri bukan tanpa sebab bahwa kelak ia kemudian mengembangkan kariernya sebagai seorang ilmuwan keislaman di wilayah Melayu dan hampir semua karya-karyanya ditulis dalam bahasa Melayu. Pamannya, Muhammad al-Hamid menjadi pengajar di Aceh di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah, bersamaan waktunya di saat Hamzah Fansuri menjadi penyair Sufi agung yang pertama- tama merumuskan doktrin Sufi dan metafisika dalam bahasa Melayu, yang disusul oleh muridnya Syamsuddin al-Sumatrani. Selama lima dasawarsa sebelum Arraniri datang ke Aceh berkumpullah sejumlah ulama di Aceh yang masyhur yang disebutkan dalam bukunya Bustan al- Salatin, antara lain Syekh Abu al-Khayr ibn Hajar, Syekh Muhammad al-Yamani, Muhammad al- Hamid, dan sejumlah ulama yang lain. Al-Attas juga memberikan daftar nama 69 buah buku yang dijadikan rujukan oleh Arraniri dalam penulisan buku-buku Tasaufnya. Dengan lengkapnya daftar karangan-karangan Arraniri serta buku-buku rujukan yang dikutipnya, al-Attas ingin menunjukkan betapa luar biasa kayanya pengetahuan yang dimiliki oleh Arraniri yang memungkinkan pembacanya mengetahui alam pemikiran para ulama pada masa jayanya. Dalam bukunya A Commentary on al-Hujjat al-Siddiq of Nuruddin al-Raniri, hal. 29, al-Attas secara jenius berupaya memahami pemikiran Arraniri sebagai kasus yang dapat menunjukkan kehebatan pemikiran para ulama pembangun intelektualisme Islam di nusantara. Dengan menelusuri pemikiran para ulama pendahulu Arraniri, seperti Hamzah Fansuri dan Samsuddin al-Sumatrani serta ulama seangkatannya, al-Attas dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ulama pada periode antara 1590 sampai dengan 1630 para ulama di nusantara telah menetapkan pilihan standar atau pilihan yang baku yaitu: pemikiran Imam Syafii dalam bidang fiqh, pemikiran al-Asyari dalam bidang tauhid dan pandangan-pandangan al- Juneid dalam bidang Tasauf. Itulah sebabnya dasar-dasar intelektualisme dan kerohanian Islam di nusantara diwarnai hampir sepenuhnya pandangan dan pemikiran ketiga ulama besar tersebut, karena pandangan ketiganyalah yang dipilih oleh para ulama di nusantara ini. Pada halaman xv dalam bukunya itu al-Attas menegaskan: My purpose in writing this commentary is twofold. In the first instance, it is to demonstrate that the unity of ideas in the world of Islam pertaining to the intellectual interpretation of the nature of reality was not confined only to particular parts of that world, but to the whole of it. An integrated metaphysical system formulated to explain the nature of God, of the universe, of man, of creation, of knowledge in short, of reality as a whole was known also in the Malay world. In the second instance , the vision of the nature of reality derived from the intuition of existence as experienced by the masters among the men of discerment can indeed be formulated in rational and theoretical terms needed as a foundation for an Islamic philosophy of science. Para ulama terdahulu, selain jenius mewariskan dasar-dasar intelektualisme Islam Indonesia yang tangguh juga mewariskan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang seringkali dijuluki tradisional, namun ternyata memudahkan para ulama, para asatidz dan para dai (tokoh-tokoh utama penganjur dan pengawal Islam) generasi berikutnya untuk meneruskannya. Begitu mudahnya cara para ulama terdahulu mendirikan pesantren, madrasah, dan perguruan- perguruan tinggi Islam sehingga begitu mudahnya langkah-langkah tersebut dapat ditiru oleh para ulama sekarang. Warisan ulama dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di nusantara yang telah mencapai jumlah 16.000 pesantren dan sekitar 60.000 12. madrasah merupakan jaringan pendidikan Islam yang paling besar dan paling luas dibandingkan dengan jaringan serupa di negeri-negeri Muslim yang lain. Dan itulah rahasianya, para ulama mampu mengislamkan sekitar 90% penduduk di nusantara yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 200 juta orang. Peran ulama generasi berikutnya yang selama 400 tahun kemudian mampu menjaga serta mengembangkan tradisi tersebut sehingga penduduk nusantara tetap menjadi penduduk Muslim terbesar di dunia sampai sekarang (dengan jumlah lebih dari 200 juta) yang kini tersatukan dalam satu pemerintahan, juga sudah seharus dikagumi oleh generasi sekarang. Umat Islam di wilayah nusantara ini memang pantas sangat bangga beruntung mewarisi kebudayaan Islam Melayu yang mengagumkan, dan kita berkumpul saat ini tentu bukan hanya mengagumi dan mengenang jasa para ulama, melainkan juga ingin memperkaya dan memajukan peradaban Islam Melayu ke masa depan. Di tengah-tengah percaturan antar peradaban yang semakin intensif dewasa ini Peradaban Islam Melayu tidak boleh terjepit dan apa lagi hancur. Peradaban Barat saat ini sedang giat-giatnya memperkuat dominasinya dalam percaturan peradaban dunia. Peradaban Islam di Timur Tengah, Peradaban Cina dan India juga sedang bangun. Mampukah kita memperkuat diri dan menjadikan ulama kita kembali berperan besar sebagai tulang punggung kemajuan kemajuan peradaban Islam Melayu ke masa depan? Kita punya bibit dan akar peradaban sendiri yang sangat kuat, dan bila lebih bertumpu kepada peradaban bangsa lain dalam mengarungi masa depan, kita justru akan hancur. Ujian- ujian berat yang menimpa peradaban Islam pada periode abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 memang sangat berat. Buku-buku ilmu pengetahuan yang menyimpan pemikiran para ulama dan tersimpan di perpustakaan di Baghdad dihancurkan oleh pasukan Hulaghu Khan pada tahun 1258. Buku-buku perpustakaan dilemparkan ke sungai Tigris dan Euphrat. Yang tersimpan di perpustakaan di Cordoba jatuh ke tangan para ilmuwan di Eropa. Buku-buku tersebut, karena belum ada percetakan, ditulis tangan hanya sebanyak satu atau dua kopi saja. Para ilmuwan Muslim yang kehilangan buku-buku tersebut banyak yang kemudian pindah ke wilayah India dan Asia Tenggara dan mampu membangun peradaban Islam di wilayah-wilayah baru tersebut. Dengan datangnya para ulama dari wilayah Timur Tengah melalui India tersebut, penduduk Melayu di kepulauan nusantara berangsur-angsur memeluk agama Islam dan setelah semakin kuat posisi ekonomi, kultural dan politiknya, mampu membangun peradaban Melayu yang hebat seperti yang kita warisi sekarang. Namun demikian, malapetaka baru muncul. Sebelum pemikir-pemikir besar seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Arraniri, dan Abdurrauf Assingkili, cukup waktu untuk mampu membangun kader-kader pada generasi berikutnya, kekuatan asing (Portugis, Belanda, Inggris, dan bangsa-bangsa lain) dari Eropa melumpuhkan kekuatan ekonomi dan pemerintahan di wilayah nusantara yang mengakibatkan penduduk generasi pertengahan abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-20 menjadi bangsa yang terjajah. Selama kurang lebih 350 tahun terjajah, penduduk nusantara yang selama ribuah tahun menjadi bangsa bahari, terisolasi dalam percaturan dengan dunia luar. Pada periode penjajahan tersebut terjadi stagnasi pemikiran. Namun demikian, para ulama pada masa penjajahan masih mampu berjasa sebagai penjaga dan pengawal kelangsungan hidup serta integritas peradaban Melayu. Dinamika kemajuan peradaban Melayu merupakan 13. kesatuan tiga serangkai, yaitu, Islam, kemelayuan dan kemampuan tinggi dalam perdagangan. Saatnya ulama generasi baru, setelah bebas dari penjajahan dan eksploitasi ekonomi asing, untuk juga dapat melepaskan diri dari belenggu stagnasi pemikiran dan ilmu pengetahuan; namun tetap dengan mempertahankan tradisi pemikiran para ulama terdahulu yang memang masih lebih baik, dengan mengambil tradisi baru, meskipun dari peradaban luar, yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk memperkaya peradaban Melayu ke depan. MENGENANG SYEKH NURULLAH Untuk memperkuat kebanggaan masyarakat Aceh terhadap besarnya jasa ulama Aceh dalam pembangunan ilmu pengetahuan, bahasa Melayu dan Indonesia, serta peranan mereka dalam penentuan arah kehidupan pemerintahan penduduk Melayu dan Indonesia kedepan, saya ingin menceritakan cukup panjang tentang perjalanan hidup seorang alim kelahiran Pasei sekitar 55 tahun sebelum Hamzah Fansuri. Seorang alim tersebut bernama Syekh Nurullah, yang pada usianya sekitar 29 tahun ia meninggalkan Pasei karena tidak tahan lagi hidup di Pasei karena telah dikuasai oleh Portugis. Ia pergi menunaikan ibadah haji dan menetap di Makkah selama tiga tahun untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Pulangnya ke nusantara pada tahun 1524 tidak menuju ke Pasei, melainkan ke Demak meskipun Pasei waktu itu sudah dibebaskan dari pendudukan Portugis oleh Sultan Ali Mughayat Syah yang baru muncul sebagai orang kuat dan berhasil mengembangkan Kesultanan Aceh. Pilihan Syekh Nurullah untuk berlabuh di Demak mungkin terkait dengan situasi dan perkembangan politik serta perdagangan yang sangat cepat berubah di wilayah nusantara. Portugis mampu mengalahkan Adipati Unus yang menyerang Malaka dengan lebih dari 30 kapal jung besar pada tahun 1513 dan sekitar 13.000 pasukan. Sejak itu Portugis menguasai medan perdagangan rempah-rempah di seluruh nusantara. Kesultanan Aceh memang mulai ramai dengan pindahnya sejumlah ulama yang tidak krasan di Malaka setelah diduduki Portugis dan memperoleh kesempatan untuk mengatur perdagangan rempah-rempah di wilayah kekuasaan Aceh. Sebagaimana telah diuraikan di atas, sewaktu Portugis dibawah pimpinan de Brito menyerang Kesultanan Aceh dapat digagalkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah di laut lepas. Dengan hitungan mundur, tanggal lahir Syekh Nurullah dapat diperhitungkan, mungkin antara tahun 1490 dan 1495. Perkiraan itu dihitung dari tahun meninggalnya yang menurut catatan Dr. De Graaf dan Dr. Pigeaud, dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, hal. 151, ia meninggal pada tahun 1570 dalam usia yang sudah sangat tua dalam kedudukan sebagai Sultan Cirebon dan seorang alim besar yang masuk dalam kelompok Walisongo. Keputusannya untuk berlabuh di Demak nampaknya telah diperhitungkannya dengan sangat matang dengan tujuan untuk memaksimalkan peranannya sebagai ilmuwan dan bakatnya sebagai politisi Muslim. Sayekh Nurullah disambut dengan hangat dan penuh hormat oleh Raja Demak, Trenggono yang waktu itu belum bergelar sultan. Meskipun usianya baru sekitar antara 30-34 tahun, sejak kedatangannya langsung mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Menurut catatan de Graaf dan Pigeaud, Syekh diberi kewenangan untuk menunjuk Imam Besar Masjid Agung Kraton Demak ke-4, Pengulu Rahmatullah. Imam ke-3 masih bergelar Kyai Pambayun. Yang pertama dan kedua bergelar ratu Demak, suatu gelar yang menunjukkan belum mapannya nomenklatur jabatan pejabat- 14. pejabat istana yang berkaitan dengan tugas-tugas keislaman. Jabatan pengulu yang ditetapkan Syekh Nurullah menunjukkan pengaruh nomenklatur Melayu yang diperkenalkan oleh Syekh Nurullah. Pada tahun berikutnya ia bahkan dinikahkan dengan saudara perempuan Raja. Tahun-tahun kehidupan Syekh Nurullah yang diuraikan oleh Tome Pires dan orang-orang Portugis lainnya cukup rinci dan berkisar tentang semangatnya menyebarkan agama Islam kepada penduduk Jawa Barat serta kelihaian dan keberhasilannya sebagai politisi. Pengalaman hidup syekhpun pada masa mudanya langsung berbenturan dengan keberadaan Portugis. Selama tiga tahun di Makkah itu ia kemungkinan mengetahui perkembangan pemerintahan Kesultanan Turki di Asia Depan dan Eropa Timur. Selang beberapa bulan setelah menjadi ipar Raja Trenggono, beliau menganjurkan kepada raja Demak agar bertindak sebagai raja Islam sejati dengan pertama-tama merubah gelarnya dengan sebutan Sultan bagi kakak iparnya itu, dan dalam menjalankan tugas kekuasaan-nya sebagai seorang Sultan, perlu melaksanakan panggilan Islam untuk mengislamkan penduduk di wilayah Banten, dan mengusir Portugis yang kafir di Sunda Kelapa. Masa-masa itu adalah masa pembentukan kebudayaan, bahasa dan sastra Melayu Islam, dan nampak dengan jelas dari langkah-langkah Syekh Nurullah memperkenalkan sejumlah istilah yang telah baku ke dalam kazanah kata-kata dalam bahasa Jawa, seperti sultan, rahmatullah, pengulu dan kafir. Seluruh usul Syekh Nurullah disetujui oleh Sultan Trenggana. Dengan bantuan personil dan logistik dari Sultan Trenggono yang cukup memadai, Syekh Nurullah berlayar dari Demak menuju Banten pada tahun 1525. Beliau berhasil meyakinkan bupati Sunda, untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas kota pelabuhan tersebut dan membantu Syekh Nurullah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa merupakan kota pelabuhan tua yang sangat penting bagi perdagangan Kerajaan Pejajaran. Pengusiran Portugis di Sunda Kelapa berhasil dengan gemilang pada tahun 1527 melalui pertempuran yang cukup sengit. Sebagai rasa hormat atas kemenangannya mengusir Portugis, masyarakat Sunda dan Betawi memberi kehormatan kepada Syekh Nurullah dengan gelar Fatahillah, sedangkan orang Portugis menamakannya Falatehan. Sebagai tanda bahwa perebutan Sunda Kelapa tersebut sungguh sangat penting bagi pengemba-ngan agama Islam, kota itu kemudian diberi nama baru Jayakarta, dan sekarang bernama Jakarta. Itulah sebabnya masyarakat Betawi menyebut Syekh Nurullah juga sebagai Pangeran Jayakarta. Pada tahun 1528, Sultan Trenggono menghadiahkan sepucuk meriam besar buatan Demak yang dibubuhi tahun pembuatannya atas keberhasilan Syekh Nurullah menguasai Banten dan menjadikannya sebagai pelabuhan dagang yang maju. Meriam tersebut pada paruh pertama abad ke-20 masih dapat dilihat di Banten, di Kampung Karang Antu. Dengan telah mantapnya Islamisasi Banten dan Jayakarta, Syekh Nurullah tidak merasa perlu melakukan kontak diplomasi resmi untuk memperluas langkah Islamisasi- nya ke pedalaman dengan penguasa Pakuan di Bogor atau Kerajaan Pajajaran di Sumedang. Dengan menguasai seluruh pantai utara Jawa Barat, beliau yakin bahwa Islamisasi ke pedalaman dapat berjalan secara otomatis tanpa penggunaan kekuatan militer. Misi-misi diplomatik dalam proses Islamisasi ke pedalaman pun tidak perlu dipimpinna secara langsung. Oleh karena itu beliau menggunakan strategi yang lebih lihai dengan cara menelusuri dan mengontrol seluruh perdagangan rempah-rempah di sepanjang pantai Jawa Barat antara Banten dan Cirebon dan sekaligus memperkuat keislaman penduduk-penduduk pantai. Dua anak laki-lakinya ditugasi masing-masing untuk memimpin Cirebon dan Banten sedangkan Syekh Nurullah secara berkala 15. mondar-mandir Banten dan Cirebon yang sejak permulaan abad ke-16 telah menjadi kota dagang Cina yang sudah masuk Islam serta telah termasuk bagian daerah Kesultanan Demak. Namun dengan pesatnya kemajuan Banten dan Sunda Kelapa sebagai kota dagang merica beliau lebih mencurahkan waktunya di Banten dan mohon kepada Sultan Trenggono untuk menempatkan putra pertamanya yang telah menikah dengan putri Sultan Trenggono menetap dan memimpin Cirebon. Putra pertama ini meninggal sangat muda yang diperkirakan oleh para pedagang Portugis pada tahun 1552. Kesedihan Syekh Nurullah ditinggal mati putra pertamanya terobati karena keluarga Sultan Trenggono segera menikahkan Hasanuddin, putra kedua Syekh Nurullah dengan putri Sultan Trenggana yang lain dan menyetujui pengangkatan Hasanuddin sebagai Sultan Banten yang pertama yang wilayahnya meliputi Sunda Kelapa. Syekh Nurullah, dengan pertimbangan ingin lebih membahagiakan istrinya, yang juga adik perempuan Sultan, untuk diizinkan tinggal lebih dekat ke Kraton Demak. Oleh karena itu Syekh mohon ditugaskannya sebagai pengelola Cirebon, dengan tetap bersikap sebagai bawahan Demak. Terlepas dari soal sejauh mana kuatnya otoritas yang dimiliki Syekh Nurullah sebagai penguasa Cirebon, namun hubungan Cirebon dengan penguasa Demak tetap mesra, bahkan saat terjadi persaingan internal di Demak. Beliau mendahulukan kedudukannya sebagai sesama anggauta keluarga kerajaan yang netral serta berupaya menjaga kehormatannya sebagai salah seorang aulia dari Walisongo dengan gelar Sunan Gunungjati. Bagi beliau, gelar sebagai salah seorang aulia lebih dipentingkan dari pada kehormatan beliau sebagai penguasa yang independen dalam memimpin Cirebon. Sewaktu Demak mengalami kehancuran dan pusat kerajaan pindah ke Pajang, kesultanan Cirebon kemungkinan tidak perlu menempatkan diri sebagai bawahan Pajang. Namun demikian, Syekh Nurullah lebih menempatkan diri sebagai seorang alim dan memberikan perhatian yang lebih besar sebagai pendidik. Memang pamornya sebagai pendiri kesultanan Cirebon tidak setinggi putranya Hasanuddin sebagai Sultan Banten, yang bahkan mampu melebarkan kekuasaannya ke wilayah Lampung. Popularitas Sunan Gunungjati sebagai seorang alim yang paling dihormati di wilayah Jawa Barat, sampai saat ini belum ada yang menandinginya. Kenyataan ini menunjukkan kelihaian beliau bermain politik sehingga Cirebon aman dari pergolakan internal, sehingga darah keturunannya sebagai pemilik kraton Cirebon masih tetap terjaga sampai sekarang. Dan dari penuturan orang-orang Portugis ternyata pada abad ke-16 perdagangan merica penting di kota-kota pelabuhan Jawa Barat, termasuk Cirebon. Sepak terjang Syekh Nurullah yang saya ketahui seperti diuraikan diatas merupakan rekonstruksi untuk dapat membangun hipotesis tingginya ketokohan serta kekokohan posisi para ulama pada periode awal-awal Islamisasi di Nusantara. Memang kasus Syekh Nurullah bertumpu kepada laporan-laporan kegiatan politiknya yang dituturkan oleh orang-orang Portugis dan hikayat-hikayat tradisional. Ada satu warisan yang tentunya sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang dari seorang ilmuwan tangguh sekaliber Syekh Nurullah. Seperti Ibnu Khaldun, yang sejak mudanya bergelut dalam arena kekuasaan politik dengan modal ilmu pengetahuan yang dimilikinya fiqh siasah, dapat mewariskan karya besar yang mengagumkan yaitu Muqoddimah Ibnu Khaldun yang ditulisnya setelah karier politiknya hancur pada usia 53 tahun. Syekh Nurullah tetap memimpin jabatan sebagai sultan sampai meninggalnya pada usia sekitar atau hampir 80 tahun. Peninggalan dalam kehidupan akademik juga jelas spektakuler: Islamisasi 16. penduduk Jawa Barat yang diawali oleh Syekh Nurullah dari Banten, Sunda Kelapa, dan selanjutnya Cirebon, wilayah Jawa Barat kini juga memiliki jumlah pesantren dan madrasah yang secara proporsional dengan rasio jumlah penduduk terbesar nomor dua setelah Aceh; dan pada abad ke-19 melahirkan seorang Syekh Nawawi al-Banteni, yang pada buku-buku karangannya, khususnya kitab tafsirnya yang berjudul Muragh Labib di covernya tertulis: Attalif, Syekh Nawawi al-Banteni, Sayyid Ulama al-Hijaz yang terbit di Kairo. Dengan demikian, murid Syekh Nurullah, dari generasi antara tahun 1525 dan tahun 1552 di Banten secara turun-temurun sampai abad ke-19, ada yang muncul menjadi gurunya para ulama di Hijaz. MELAYU, ISLAM DAN PERDAGANGAN Dalam pengembangan bahasa Melayu, tercermin dari terlibatnya seluruh wilayah kota- kota pantai di Jawa Barat dalam hubungan dagangnya, baik interinsuler maupun internasional, ke seluruh wilayah nusantara serta dengan negara-negara Asia Tenggara, India, Cina dan Timur Tengah. Pada periode antara tahun 1400 dan 1650, Asia Tenggara berkembang, oleh Prof. Anthony Reid ditandai sebagai: South-East Asia in the Age of Commerce; sedangkan oleh Prof. Anthony Johns, Samudra India antara Lautan Merah dan pantai Sumatra dijuluki sebagai The Second Arabic Mediterranean Sea. Hal itu berarti, penduduk Melayu terlibat langsung dalam percaturan dan akulturasi dengan berbagai bahasa secara intensif yang digunakan di wilayah Asia Tenggara yang memacu para sarjana bahasa dan sastra di kalangan penduduk Melayu merekonstruksi pembentukan dan pengembangan bahasa serta satra Melayu. Secara otomatis, bahasa dan sastra Melayu mengalami proses Islamisasi dan Arabisasi secara intensif pula. Demikian pula tulisan dan abjad Melayu secara menyeluruh menjadi abjad dan tulisan Arab Jawi. Karena para ulama menjadi tulang-punggung proses Islamisasi dimana bahasa Arab menjadi perantara hubungan lisan dan tulisan yang paling penting antar para pedagang dan dalam kegiatan pendidikan, maka para ulama memegang peran penting dalam pengembangan bahasa dan sastra Melayu. Kedatangan Syekh Nurullah yang tidak mengetahui bahasa Jawa sama sekali tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, bahasa Melayu sudah pasti menjadi bagian dari alat percakapan antar ilmuwan dan pemimpin pemerintahan di lingkungan Kerajaan Demak, Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Cerita tentang Pasei sebagai pusat studi Islam yang tinggi mutunya sejak abad ke-13 sudah pasti juga diketahui dengan saksama di kalangan para ulama dan pemimpin di Demak. Dalam waktu beberapa tahun ini sejumlah arkeolog sedang melakukan penggalian di sebuah situs di Lobu Tua, Barus. Disamping itu pada bulan Oktober 1999, juga dalam rangka penelitian arkeologi yang dilakukan oleh satu tim IndonesiaPerancis di situs Barus diselenggarakan kegiatan pembacaan inskripsi-inskripsi pada sekitar 40 batu nisan berbahasa Arab dan satu nisan berbahasa Parsi. Pada salah satu nisan tersebut terdapat nama Fansur yang ditulis Fansuri, dan setelah diteliti, nisan sebuah kuburan seorang yang bernama Shaykh Hamza b. Abd Allah al-Fansuri yang meninggal pada tanggal 9 Rajab 933, yang berarti 11 April 1527. Pada waktu teks itu disalin, nisan yang bertuliskan inskripsi tersebut berada dalam pekuburan Bab Mala di Makkah. Inskripsi tersebut tentu membuat kita semua pusing kepala dan menimbulkan pertanyaan: apakah ada dua nama Hamza bin Abdullah al-Fansuri. Kalau hanya satu kenapa inskripsi tersebut bertahun 1527, dan berada di pekuburan elit tempat Siti Khadijah dan Siti Fathimah 17. dimakamkan? Namun, paling tidak, ini suatu indikasi bahwa seorang putra Barus yang dimakamkan di pekuburan Bab Mala, Makkah, yang meninggal pada tahun 1527 adalah seorang alim agung yang sangat dihormati masyarakat elit di Makkah Penggalian di situs Barus juga memberikan beberapa hasil yang menakjubkan. Cukup banyak batu nisan telah ditemukan yang menunjukkan bahwa sejumlah ulama yang meninggal di Barus dari awal abad 10 s/d abad 16, adalah ulama-ulama beberapa generasi yang dapat diperkirakan cukup tinggi ilmu pengetahuannya yang memungkinkan hasil didikannya menjadi ulama hebat yang mungkin dapat menjadi tokoh-tokoh pemikir yang sangat penting di wilayah nusantara. Oleh karena itu, seorang Hamzah Fansuri yang lahir di Barus (sekitar) paruh pertama abad 16, dapat memperoleh pendidikan tinggi dalam berbagai ilmu keislaman, bahasa dan sastra Arab serta bahasa dan sastra Melayu. Karya-karya Hamzah Fansuri sangat monumental. Oleh karena itu, kalau tidak memperoleh pendidikan tinggi yang cukup berbobot, bagaimana mungkin beliau dapat menjadi seorang alim, Sufi, dan sekaligus sarjana pengembang bahasa dan sastra Melayu. Orang-orang yang mengunjungi Masjidil Haram sebelum dirombak seperti sekarang, masih dapat menemukan tulisan-tulisan Arab Jawi dan bahasa Melayu Jawi diatas pintu toilet yang berbunyi Kakus untuk perempuan dan Kakus untuk Laki-Laki yang menunjukkan betapa kuatnya maktab wukalah al-Jawi di Makkah pada abad ke-19. Sayed Muhammad Naquib al-Attas, telah menulis sebuah buku berjudul A Commentary on the Hujjat al-Siddiq of Nur al-Din al-Raniri. Dalam buku itu dimuat pula karya Arraniri yang ditulis dalam tulisan Arab Jawi tersebut. Dengan mempelajari riwayat hidup seorang alim sekaliber Nurullah (Sunan Gunung Jati), Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Arraniri dan Abdurrauf As-Singkili) betapa hebatnya para ulama terdahulu dalam upaya mengubah alam pemikiran masyarakat di nusantara ini dari bangsa yang beragama Hindu- Buddhis menjadi masyarakat Muslim yang secara turun-temurun kini telah kita warisi sebagai bangsa yang paling banyak penduduknya yang beragama Islam. Para ulama ilmuwan tersebut telah berkarya besar mengubah dan mengganti huruf, struktur dan fonetik bahasa Melayu kuno dengan dasar-dasar bahasa Sansekerta, menjadi huruf Arab Jawi, struktur dan fonetik bahasa Melayu Islam. Karya-karya para ulama itu menunjukkan kualitas pendidikan tinggi yang diperoleh dari ulama seniornya serta selama beberapa generasi sebelumnya yang telah menjadikan Barus sebagai pusat penyebaran dan pendidikan tinggi Islam antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. (Lihat Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, hal. 54, oleh: Sayed Muhammad Naquib Al-Attas). Terciptanya tulisan atau huruf Arab Jawi dan bahasa Melayu sesungguhnya merupakan gambaran betapa perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam bidang kehidupan keagamaan, sains, kebudayaan, pandangan yang menyangkut wilayah alam ke-Tuhanan dan duniawiyah telah secara revolusioner terbangun bagi masyarakat di nusantara yang dimotori oleh tokoh-tokoh utama sekaliber Hamzah Fansuri, Syamsuddin Assumatrani, Nuruddin Arraniri dan Abdurrauf Assingkili. Zamakhsyari Dhofier 18. Tabel 1: Rasio penduduk, jumlah pesantren dan lembaga pendidikan N o PROPINSI Jumlah Penduduk (2004) PP Jumlah Santri RA MI MTs MA MI+MTs+MA PTA 1 Aceh 4.075.599 852 244.418 49 560 245 139 944 125 2 Sumut 12.068.731 178 62.699 3 571 829 359 1.759 - 3 Sumbar 4.528.242 152 33.756 17 112 354 155 621 - 4 Riau 5.679.643 120 37.554 14 371 484 174 1.029 9 5 Jambi 2.619.553 116 29.245 16 1.350 250 103 1.703 4 6 Sumsel 6.596.057 203 56.001 51 432 335 112 879 12 7 Bengkulu 1.541.551 34 8.012 7 97 70 32 199 1 8 Lampung 7.028.388 342 73.866 62 703 495 163 1.361 27 9 Bangka Balitung 1.012.655 24 5.267 5 46 40 15 101 2 10 DKI Jakarta 8.725.630 75 30.727 12 501 229 71 801 - 11 Jabar 38.472.185 4.548 802.063 458 3.223 1.799 604 5.626 242 12 Banten 9.083.144 1.426 197.959 104 904 554 200 1.658 64 13 Jateng 32.397.431 2.014 461.735 183 3.769 1.342 390 5.501 271 14 DIY 3.220.808 160 32.952 9 148 85 34 267 47 15 Jatim 36.396.345 3.200 946.945 783 7.448 2.286 928 10.662 424 16 Bali 3.393.620 87 9.712 12 46 21 10 77 6 17 NTB 4.076.040 287 131.355 52 563 507 222 1.292 15 18 NTT 4.139.206 17 1.361 1 119 49 17 185 2 19 Kalbar 4.010.338 90 19.687 7 248 188 64 500 7 20 Kalteng 1.867.231 56 13.552 9 218 107 40 365 1 21 Kalsel 3.219.398 174 62.928 23 591 276 108 975 11 22 Kaltim 2.761.575 90 14.935 11 100 122 54 276 3 23 Sulut 2.154.235 10 1.708 3 38 39 12 89 24 Sulteng 2.245.242 64 10.653 11 81 165 60 306 8 25 Sulsel 8.342.083 200 53.192 47 642 558 248 1.448 18 26 Sultera 1.911.103 57 9.974 12 68 99 51 218 4 27 Gorontalo 896.004 19 4.241 4 49 50 20 119 - 28 Maluku 1.238.812 13 2.984 1 81 43 16 140 - 29 Maluku Utara 869.235 14 5.123 4 51 60 29 140 - 30 Papua 2.502.262 31 4.589 4 34 25 9 68 2 Jumlah 217.072.346 14.653 3.369.193 1.974 23.164 11.706 4.439 39.309 1.305 19. Tabel 2: Jumlah madrasah negeri dan swasta Propinsi Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah Jumlah Negeri Swasta Jumla h Negeri Swasta Jumla h Negeri Swasta Jumla h Aceh 424 136 560 101 144 245 56 83 139 944 Sumut 119 452 571 55 774 829 35 324 359 1.759 Sumbar 56 56 112 106 248 354 37 118 155 621 Riau 18 353 371 29 455 484 14 160 174 1.029 Jambi 27 1.323 1.350 50 200 250 13 90 103 1.703 Sumsel 33 399 432 31 304 335 16 96 112 879 Bengkulu 32 65 97 19 51 70 8 24 32 199 Lampung 48 655 703 24 471 495 12 151 163 1.361 Bangka Balitung 6 40 46 7 33 40 3 12 15 101 DKI Jakarta 18 483 501 28 201 229 11 60 71 801 Jabar 74 3.149 3.223 138 1.661 1.799 66 538 604 5.626 Banten 16 888 904 27 527 554 18 182 200 1.658 Jateng 106 3.663 3.769 116 1.226 1.342 61 329 390 5.501 DIY 19 129 148 34 51 85 15 19 34 267 Jatim 138 7.310 7.448 180 2.106 2.286 82 846 928 10.662 Bali 12 34 46 6 15 21 3 7 10 77 NTB 23 540 563 21 486 507 12 210 222 1.292 NTT 12 107 119 11 38 49 4 13 17 185 Kalbar 14 234 248 18 170 188 6 58 64 500 Kalteng 28 190 218 15 92 107 7 33 40 365 Kalsel 137 454 591 73 203 276 34 74 108 975 Kaltim 6 94 100 18 104 122 9 45 54 276 Sulut 7 31 38 7 32 39 2 10 12 89 Sulteng 19 62 81 26 139 165 7 53 60 306 Sulsel 47 595 642 39 519 558 28 220 248 1.448 Sultera 11 57 68 27 72 99 7 44 51 218 Gorontalo 2 47 49 7 43 50 3 17 20 119 Maluku 13 68 81 9 34 43 4 12 16 140 Maluku Utara 15 36 51 13 47 60 4 25 29 140 Papua 4 30 34 4 21 25 2 7 9 68 1.484 21.680 23.164 1.239 10.467 11.706 579 3.860 4.439 39.309