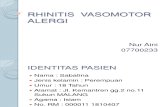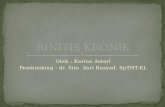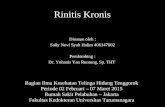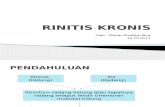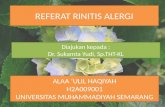Referat Rinitis Vasomotor
-
Upload
izatul-farhanah -
Category
Documents
-
view
682 -
download
19
Transcript of Referat Rinitis Vasomotor
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan referat berjudul Rinitis Vasomotor ini tepat pada waktunya. Referat ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas kepaniteraan klinik di bagian Telinga Hidung dan Tenggorok RSUD Karawang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yuswandi Affandi Sp.THT dan Dr. Ivan Djajalaga, M.Kes, Sp.THT selaku dokter pembimbing dalam kepaniteraan klinik THT ini dan rekan-rekan koas yang ikut membantu memberikan semangat dan dukungan moril. Penulis menyadari bahwa referat ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga referat ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dalam bidang THT khususnya dan bidang kedokteran yang lain pada umumnya.
Karawang, 12 September 2011
Penulis
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan
1
3
BAB II
Anatomi Fisiologi
4 8
BAB III
Rinitis Vasomotor Definisi Epidemiologi Etiologi Patofisiologi Gejala Klinis Diagnosis Penatalaksanaan Komplikasi Prognosis 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16
BAB IV
Kesimpulan
BAB V
Daftar Pustaka
17
2
BAB I PENDAHULUAN Gangguan vasomotor adalah terdapatnya gangguan fisiologik lapisan mukosa hidung yang disebabkan oleh bertambahnya aktivitas parasimpatis. Rinitis vasomotor adalah gangguan pada mukosa hidung yang ditandai dengan adanya edema yang persisten dan hipersekresi kelenjar pada mukosa hidung apabila terpapar oleh iritan spesifik. Rinitis vasomotor adalah suatu keadaan idiopatik yang didiagnosis tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, perubahan hormonal (kehamilan, hipertiroid), dan pajanan obat (kontrapsepsi oral, antihipertensi, B-bloker, aspirin, klorpromazin dan obat topikal hidung dekongestan) Rinitis ini digolongkan menjadi non-alergi bila adanya alergi/alergen spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan alergi yang sesuai (anamnesis, tes cukit kulit, kadar antibodi IgE spesifik serum). Kelainan ini disebut juga vasomotor catarrh, vasomotor rinorhea, nasal vasomotor instability, atau juga non-allergic perennial rhinitis. Rinitis vasomotor mempunyai gejala yang mirip dengan rinitis alergi sehingga sulit untuk dibedakan. Pada umumnya pasien mengeluhkan gejala hidung tersumbat, ingus yang banyak dan encer serta bersin-bersin walaupun jarang. Etiologi yang pasti belum diketahui, tetapi diduga sebagai akibat gangguan keseimbangan fungsi vasomotor dimana sistem saraf parasimpatis relatif lebih dominan. Keseimbangan vasomotor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlangsung temporer, seperti emosi, posisi tubuh, kelembaban udara, perubahan suhu luar, latihan jasmani dan sebagainya, yang pada keadaan normal faktor-faktor tadi tidak dirasakan sebagai gangguan oleh individu tersebut. Diagnosis dapat ditegakkan dengan anamnesis yang cermat, pemeriksaan THT serta beberapa pemeriksaan yang dapat menyingkirkan kemungkinan jenis rhinitis lainnya. Penatalaksanaan rinitis vasomotor bergantung pada berat ringannya gejala dan dapat dibagi atas tindakan konservatif dan operatif.
3
BAB II II.1 ANATOMI HIDUNG Hidung luar berbentuk piramid dengan bagian-bagiannya dari atas ke bawah yaitu pangkal hidung (bridge), batang hidung (dorsum nasi), puncak hidung (tip), ala nasi, Columela dan lubang hidung (nares anterior). Hidung luar dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kerangka tulang terdiri dari tulang hidung (os nasal), prosesus frontalis os maksila, dan prosesus nasalis os frontal. Sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian bawah hidung yaitu sepasang kartilago nasalis lateralis superior, sepasang kartilago nasalis lateralis inferior yang disebut juga sebagai kartilago alar mayor dan tepi anterior kartilago septum. Rongga hidung atau kavum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang di pisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi kavum nasi kanan dan kiri. Pintu atau lubang masuk kavum nasi bagian depan disebtu nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior (koana) yang menghubungkan kavum nasi dengan nasofaring. Bagian dari kavum nasi yang letaknya sesuai dengan ala nasi, tepat di belakang nares anterior, disebut vestibulum. Vestibulum ini dilapisi oleh kulit yang mempunyai banyak kelenjar sebasea dan rambut-rambut panjang disebut vibrise. Tiap kavum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior dan superior. Dinding medial hidung ialah septum nasi. Septum dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Bagian tulang adalah lamina perpendikularis os etmoid, vomer, krista nasalis os maksila dan krista nasalis os palatina. Bagian tulang rawan adalah kartilago septum (lamina kuadrangularis) dan kolumela. Septum dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periosteum pada bagian tulang, sedangkan di luarnya dilapisi oleh mukosa hidung. Pada dinding lateral terdapat 4 buah konka. Yang terbesar dan letaknya paling bawah ialah konka
4
inferior, kemudian yang lebih kecil ialah konka media, lebih kecil lagi ialah konka superior, sedangkan yang terkecil disebut konka suprema. Konka suprema ini biasanya disebut rudimenter. Konka inferior merupakan tulang tersendiri yang melekat pada os maksila dan labirin etmoid, sedangkan konka media, superior dan suprema merupakan bagian dari labirin etmoid. Diantara konka-konka dan dinding lateral hidung terdapat rongga sempit yang disebut meatus. Tergantung dari letak meatus, ada tiga meatus yaitu meatus inferior, medius dan superior. Meatus inferior terletak di antara konka inferior dengan dasar hidung dan dinding lateral rongga hidung. Pada meatus inferior terdapat muara (ostium) duktus nasolakrimalis. Meatus medius terletak di antara konka media dan dinding lateral rongga hidung. Pada meatus medius terdapat muara sinus frontal, sinus maksila dan sinus etmoid anterior. Pada meatus superior yang merupakan ruang diantara konka superior dan konka media, terdapat muara sinus etmoid posterior dan sinus sfenoid. Batas rongga hidung terdiri dari dinding inferior yang merupakan dasar rongga hidung dan dibentuk oleh os maksila dan os palatum. Dinding superior atau atap hidung sangat sempit dan dibentuk oleh lamina kribriformis, yang memisahkan rongga tengkorak dari rongga hidung. Lamina kribriformis merupakan lempeng tulang berasal dari os etmoid, tulang ini berlubang-lubang (kribrosa = saringan) tempat masuknya serabut-serabut saraf olfaktorius. Dibagian posterior, atap rongga hidung dibentuk oleh os sfenoid.
Gambar 2.1 Tulang dan tulang rawan hidung
Gambar 2.2 Bagian dalam hidung
5
PENDARAHAN HIDUNG Pendarahan untuk hidung bagian dalam berasal dari 3 sumber utama: 1. a. etmoidalis anterior, yang mendarahi septum bagian superior anterior dan dinding lateral hidung. 2. a. etmoidalis posterior ( cabang dari a. oftalmika ), mendarahi septum bagian superior posterior. 3. a. sfenopalatina, terbagi menjadi a. nasales posterolateral yang menuju ke dinding lateral hidung dan a. septi posterior yang menyebar pada septum nasi. Bagian bawah rongga hidung mendapat pendarahan dari cabang a. maksilaris interna, diantaranya ialah ujung a. palatina mayor dan a. sfenopalatina yang keluar dari foramen sfenopalatina bersama n. sfenopalatina dan memasuki rongga hidung di belakang ujung posterior konka media. Bagian depan hidung mendapat pendarahan dari cabang-cabang a. fasialis. Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang-cabang a. sfenopalatina, a. etmoid anterior, a. labialis superior dan a. palatina mayor, yang disebut pleksus Kiesselbach ( Littles area ) yang letaknya superfisial dan mudah cedera oleh trauma, sehingga sering menjadi sumber epistaksis. Vena-vena hidung mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterinya. Vena di vestibulum dan struktur luar hidung bermuara ke vena oftalmika superior yang berhubungan dengan sinus kavernosus.
Gambar 2.3 Perdarahan hidung
6
PERSARAFAN HIDUNG 1. Saraf motorik Oleh cabang n. fasialis yang mensarafi otot-otot hidung bagian luar. 2. Saraf sensoris. Bagian depan dan atas rongga hidung mendapat persarafan sensoris dari n. etmoidalis anterior, merupakan cabang dari n. nasosiliaris, yang berasal dari n. oftalmika ( N.V-1 ). Rongga hidung lainnya , sebagian besar mendapat persarafan sensoris dari n. maksila melalui ganglion sfenopalatina. 3. Saraf otonom. Terdapat 2 macam saraf otonom yaitu : a. Saraf post ganglion saraf simpatis ( Adrenergik ). Saraf simpatis meninggalkan korda spinalis setinggi T1 3, berjalan ke atas dan mengadakan sinapsis pada ganglion servikalis superior. Serabut post sinapsis berjalan sepanjang pleksus karotikus dan kemudian sebagai n. petrosus profundus bergabung dengan serabut saraf parasimpatis yaitu n. petrosus superfisialis mayor membentuk n. vidianus yang berjalan didalam kanalis pterigoideus. Saraf ini tidak mengadakan sinapsis didalam ganglion sfenopalatina, dan kemudian diteruskan oleh cabang palatina mayor ke pembuluh darah pada mukosa hidung. Saraf simpatis secara dominan mempunyai peranan penting terhadap sistem vaskuler hidung dan sangat sedikit mempengaruhi kelenjar. b. Serabut saraf preganglion parasimpatis ( kolinergik ). Berasal dari ganglion genikulatum dan pusatnya adalah di nukleus salivatorius superior di medula oblongata. Sebagai n. pterosus superfisialis mayor berjalan menuju ganglion sfenopalatina dan mengadakan sinapsis didalam ganglion tersebut. Serabut serabut post ganglion menyebar menuju mukosa hidung. Peranan saraf parasimpatis ini terutama terhadap jaringan kelenjar yang menyebabkan sekresi hidung yang encer dan vasodilatasi jaringan erektil. Pemotongan n. vidianus akan menghilangkan impuls sekretomotorik / parasimpatis pada mukosa hidung, sehingga rinore akan berkurang sedangkan sensasi hidung tidak akan terganggu.
7
4. Olfaktorius ( penciuman ) Nervus olfaktorius turun melalui lamina kribosa dari permukaan bawah bulbus olfaktorius dan kemudian berakhir pada sel-sel reseptor penghidu pada mukosa olfaktorius didaerah sepertiga atas hidung. II. 2 FISIOLOGI HIDUNG Berdasarkan teori struktural, teori evolusioner dan teori fungsional, fungsi fisiologi hidung dan sinus paranasal adalah : 1. Fungsi respirasi Udara inspirasi masuk ke hidung menuju sistem respirasi melalui nares anterior, lalu naik ke atas setinggi konka media dan kemudian turun ke bawah ke arah nasofaring. Aliran udara di hidung ini berbentuk lengkungan atau arkus. Udara yang di hirup akan mengalami humidifikasi oleh palut lendir. Pada musim panas, udara hampir jenuh oleh uap air, sehingga terjadi penguapan udara inspirasi oleh palut lendir, sedangkan pada musim dingin akan terjadi sebaliknya. Suhu udara yang melalui hidung di atur sehingga berkisar 37C. Fungsi pengatur suhu ini dimungkinkan oleh banyaknya pembuluh darah di bawah epitel dan adanya permukaan konka dan septum yang luas. Partikel debu, virus, bakteri dan jamur yang terhirup bersama udara akan disaring di hidung oleh rambut (vibrissae) pada vestibulum nasi, silia, palut lendir. Debu dan bakteri akan melekat pada palut lendir dan partikel-partikel yang besar akan dikeluarkan dengan refleks bersin. 2, Fungsi penghidu Hidung juga bekerja sebagai indra penghidu dan pengecap dengan adanya mukosa olfaktorius pada atap rongga hidung, konka superior dan sepertiga bagian atas septum. Partikel bau dapat mencapai daerah ini dnegan cara difusi dengan palut lendir atau bila menarik napas dengan kuat. Fungsi hidung untuk membantu ondra pengecap adalah untuk membedakan rasa manis yang berasal dari berbagai macam bahan,
8
seperti perbedaan rasa manis strawberi, jeruk, pisang atau coklat. Juga untuk membedakan rasa asam yang berasal dari cuka dan asam jawa. 3. Fungsi fonetik Resonansi oleh hidung penting untuk kualitas suara ketika berbicara dan menyanyi. Sumbatan hidung akan menyebabkan resonansi berkurang atau hilang, sehingga terdengar suara sengau (rinolalia). Hidung membantu proses pembentukan kata-kata. Kata dibentuk oleh lidah, bibir, dan palatum mole. Pada pembentukan konsonan nasal (m, n, ng) rongga mulut tertutup dan hidung terbuka, palatum mole turun untuk aliran udara.
9
BAB III RINITIS VASOMOTOR III. 1 DEFINISI Rinitis vasomotor adalah suatu keadaan idiopatik yang didiagnosis tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofilia, perubahan hormonal (kehamilan, hipertiroid), dan pajanan obat (kontrapsepsi oral, antihipertensi, B-bloker, aspirin, klorpromazin dan obat topikal hidung dekongestan) Rinitis ini digolongkan menjadi non-alergi bila adanya alergi/alergen spesifik tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan alergi yang sesuai (anamnesis, tes cukit kulit, kadar antibodi IgE spesifik serum). Kelainan ini disebut juga vasomotor catarrh, vasomotor rinorhea, nasal vasomotor instability, atau juga non-allergic perennial rhinitis. III. 2 EPIDEMIOLOGI Mygind ( 1988 ), seperti yang dikutip oleh Sunaryo ( 1998 ), memperkirakan sebanyak 30 60 % dari kasus rinitis sepanjang tahun merupakan kasus rinitis vasomotor dan lebih banyak dijumpai pada usia dewasa terutama pada wanita. Walaupun demikian insidens pastinya tidak diketahui. Biasanya timbul pada dekade ke 3 4. Secara umum prevalensi rinitis vasomotor bervariasi antara 7 21%. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Jessen dan Janzon ( 1989 ) dijumpai sebanyak 21% menderita keluhan hidung non alergi dan hanya 5% dengan keluhan hidung yang berhubungan dengan alergi. Prevalensi tertinggi dari kelompok non alergi dijumpai pada dekade ke 3. Sibbald dan Rink ( 1991 ) di London menjumpai sebanyak 13% dari pasien, menderita rinitis perenial dimana setengah diantaranya menderita rinitis vasomotor. Sunaryo, dkk ( 1998 ) pada penelitiannya terhadap 2383 kasus rinitis selama 1 tahun di RS Sardjito Yogyakarta menjumpai kasus rinitis vasomotor sebanyak 33 kasus ( 1,38 % ) sedangkan pasien dengan diagnosis banding rinitis vasomotor sebanyak 240 kasus ( 10,07 % ).
10
III. 3 ETIOLOGI Etilogi pasti rinitis vasomotor belum diketahui dan diduga akibat gangguan keseimbangan sistem saraf otonom yang dipicu oleh zat-zat tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan vasomotor : 1. Obat-obatan yang menekan dan menghambat kerja saraf simpatis, seperti ergotamin, chlorpromazin, obat anti hipertensi dan obat vasokonstriktor topikal. 2. Faktor fisik, seperti iritasi oleh asap rokok, udara dingin, kelembaban udara yang tinggi dan bau yang merangsang. 3. Faktor endokrin, sepeti keadaan kehamilan, pubertas, pemakaian pil anti hamil dan hipotiroidisme. 4. Faktor psikis, seperti stress, ansietas dan fatigue III. 4 PATOFISIOLOGI 1. Neurogenik (disfungsi sistem otonom) Serabut simpatis hidung berasal dari korda spinalis segmen Th 1-2, menginervasi terutama pembuluh darah mukosa dan sebagian kelenjar. Serabut simpatis melepaskan ko-transmiter noradrenalin dan neuropeptida Y yang menyebabkan vasokonstriksi dan penurunan sekresi hidung. Tonus simpatis ini berfluktuasi sepanjang hari yang menyebabkan adanya peningkatan tahanan rongga hidung yang bergantian setiap 2-4 jam. Keadaan ini disebut sebagai siklus nasi . Dengan adanya siklus ini, seorang akan mampu untuk dapat bernapas dengan tetap normal melalui rongga hidung yang berubah-ubah luasnya. Serabut saraf parasimpatis berasal nukleus salivatori superior menuju ganglion sfenopalatina dan membentuk nervus vidianus, kemudian menginervasi pembuluh darah dan terutama kelenjar eksokrin. Pada rangsangan akan terjadi pelepasan kotransmiter asetilkolin dan vasoaktif intestinal peptida yang menyebabkan peningkatan sekresi hidung dan vasodilatasi, sehingga terjadi kongesti hidung.
11
2. Neuropeptida Pada mekanisme ini terjadi disfungsi hidung yang diakibatkan oleh meningkatnya rangsangan terhadap saraf sensoris serabut C di hidung. Adanya rangsangan abnormal saraf sensoris ini akan diikuti dengan peningkatan pelepasan neuropeptida seperti substance P dan calcitonin gene-related protein yang menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular dan sekresi kelenjar. 3. Nitrik Oksida Kadar nitrik oksida (NO) yang tinggi dan persisten di lapisan epitel hidung dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau nekrosis epitel, sehingga rangsangan non spesifik berinteraksi langsung ke lapisan sub-epitel. Akibatnya terjadi peningkatan reaktifitas serabut trigeminal dan recruitment refels vaskular dan kelenjar mukosa hidung. 4. Trauma Rinitis vasomotor dapat merupakan komplikasi jangka panjang dari trauma hidung melalui mekanisme neurogenik dan/atau neuropeptida.
III. 5 GEJALA KLINIS Gejala yang dijumpai pada rinitis vasomotor kadang-kadang sulit dibedakan dengan rinitis alergi seperti hidung tersumbat dan rinore. Rinore yang hebat dan bersifat mukus atau serous sering dijumpai. Gejala hidung tersumbat sangat bervariasi yang dapat bergantian dari satu sisi ke sisi yang lain, terutama sewaktu perubahan posisi. Keluhan bersin-bersin tidak begitu nyata bila dibandingkan dengan rinitis alergi dan tidak terdapat rasa gatal di hidung dan mata. Gejala dapat memburuk pada pagi hari waktu bangun tidur oleh karena adanya perubahan suhu yang ekstrim, udara lembab, dan juga oleh karena asap rokok dan sebagainya. Selain itu juga dapat dijumpai keluhan adanya ingus yang jatuh ke tenggorok (post nasal drip ). Berdasarkan gejala yang menonjol, rinitis vasomotor dibedakan
12
dalam 2 golongan, yaitu golongan obstruksi ( blockers) dan golongan rinore (runners / sneezers ). Prognosis pengobatan golongan obstruksi lebih baik daripada golongan rinore. Oleh karena golongan rinore sangat mirip dengan rinitis alergi, perlu anamnesis dan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan diagnosisnya. III. 6 DIAGNOSIS Diagnosis umumnya ditegakkan dengan cara eksklusi, yaitu menyingkirkan adanya rinitis infeksi, alergei, okupasi, hormonal dan akibat obat. Dalam anamnesis dicari faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior tampak gambaran yang khas berupa edema mukosa hidun, konka berwarna merah gelap atau merah tua, tetapi dapat pula pucat. Hal ini perlu dibedakan dengan rinitis alergi. Permukaan konka dapat licin atau berbenjol-benjol (hipertrofi). Pada rongga hidung terdapat sekret mukoid, biasanya sedikit. Akan tetapi pada golongan rinore sekret yang ditemukan ialah serosa dan banyak jumlahnya. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan rinitis alergi. Kadang ditemukan eosinfil pada sekret hidung, akan tetapi dalam jumlah sedikit. Tes cukit kulit biasanya negatif. Kadar IgE spesifik tidak meningkat.
Riwayat penyakit
-Tidak berhubungan dengan musim. -Riwayat keluarga ( - ) - Riwayat alergi sewaktu anak-anak ( - ) - Timbul sesudah dewasa - Keluhan gatal dan bersin ( - )
Pemeriksaan THT
- Struktur abnormal ( - ) - Tanda tanda infeksi ( - ) - Pembengkakan pada mukosa ( + )
13
- Hipertrofi konka inferior sering dijumpai
Radiologi
X Ray / CT
- Tidak dijumpai bukti kuat keterlibatan sinus - Umumnya dijumpai penebalan mukosa
Bakteriologi
- Rinitis bakterial ( - )
Test alergi
Ig E total
- Normal
Prick Test
- Negatif atau positif lemah
RAST
- Negatif atau positif lemah
III. 7 PENATALAKSANAAN Penatalaksanaan pada rinitis vasomotor bervariasi, tergantung pada faktor penyebab dan gejala yang menonjol. Secara garis besar dibagi dalam: 1. Menghindari stimulus/ faktor pencetus2. Penobatan simtomatis, dengan obat-obatan dekongestan oral, cuci hidung
dengan larutan garam fisiologis, kauterisasi konka hipertrofi dengan larutan AgNO3 25% atau triklor-asetat pekat. Dapat juga diberikan kortikosteroid topikal 100-200 mikrogram. Dosis dapat ditingkatkan sampai 400 mikrogram sehari. Hasilnya akan terlihat setelah pemakaian paling sedikit selama 2 minggu. Saat ini terdapat kortikosteroid topikal baru dalam larutan aqua seperti flutikason propionat dan mometason furoat dengan pemakaian cukup satu kali sehari dengan dosis 200 mcg. Pada kasus dengan rinore berat, dapat ditambahkan antikolinergik topikal (ipatropium bromida). Saat ini sedang dalam penelitian adalah terapi desensitisasi dengan obat capsaicin topikal yang mengandung lada.
14
3. Operasi, dengan cara bedah-beku, elektrokauter, atau konkotomi parsial konka inferior. 4. Neurektomi n. Vidianus, yaitu dengan melakukan pemotongan pada n. Vidianus, bila dengan cara di atas tidak memberikan hasil optimal. Operasi tidaklah mudah, dapat menimbulkan komplikasi, seperti sinusitis, diplopia, buta, gangguan, lakrimasi, neuralgia atau anestesis infraorbita dan palatum. Dapat dilakukan tindakan blocking ganglion sfenopalatina. Prognosis pengobatan golongan obstruksi lebih baik daripada golongan rinore. Oleh karena golongan rinore sangat mirip dengan rinitis alergi, perlu anamnesis dan pemeriksaan yang teliti untuk memastikan diagnosisnya.
III. 8 KOMPLIKASI 1. Sinusitis 2. Eritema pada hidung sebelah luar 3. Pembengkakan wajah
III. 9 PROGNOSIS Prognosis dari rinitis vasomotor bervariasi. Penyakit kadang-kadang dapat membaik dengan tiba tiba, tetapi bisa juga resisten terhadap pengobatan yang diberikan. Prognosis pengobatan golongan obstruksi lebih baik daripada golongan rinore. Oleh karena golongan rinorea sangat mirip dengan rinitis alergi, perlu anamnesis dan pemeriksaan yang teliti untuk menastikan diagnosisnya.
15
BAB IV KESIMPULAN Rinitis vasomotor merupakan suatu gangguan fisiologik neurovaskular mukosa hidung dengan gejala hidung tersumbat, rinore yang hebat dan kadang kadang dijumpai adanya bersin bersin. Penyebab pastinya tidak diketahui. Diduga akibat gangguan keseimbangan sistem saraf otonom yang dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Biasanya dijumpai setelah dewasa ( dekade ke 3 dan 4 ). Rinitis vasomotor sering tidak terdiagnosis karena gejala klinisnya yang mirip dengan rinitis alergi, oleh sebab itu sangat diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang teliti untuk menyingkirkan kemungkinan rinitis lainnya terutama rinitis alergi dan mencari faktor pencetus yang memicu terjadinya gangguan vasomotor. Penatalaksanaan dapat dilakukan secara konservatif dan apabila gagal dapat dilakukan tindakan operatif.
16
DAFTAR PUSTAKA 1. Soetjipto D. Mangunkusumo E. Wardani RS. Hidung. Dalam : Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher. Editor : Seopardi EA. Iskandar N. Bashiruddin J. Restuti RD. Edisi keenam. Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007. H: 118-122 2. Irawati N. Poerbonegoro NL. Kasakeyan E. Rinitis Vasomotor. Dalam : Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher. Editor : Seopardi EA. Iskandar N. Bashiruddin J. Restuti RD. Edisi keenam. Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007. H: 135-37 3. Hilger PA. Hidung : Anatomi dan Fisiologi Terapan. Dalam : Boies Buku Ajar Penyakit THT. Editor : Adams GL. Boies LR. Higler PA. Edisi keenam. Jakarta EGC. 1997. H: 173-188 4. Hilger PA. Hidung : Penyakit Hidung. Dalam : Boies Buku Ajar Penyakit THT. Editor : Adams GL. Boies LR. Higler PA. Edisi keenam. Jakarta EGC. 1997. H: 218-195. Pharmacotherapy for Nonallergic Rhinitis. Diakses dari :
http://emedicine.medscape.com/article/874171-overview Tanggal 10 September 2010.
17