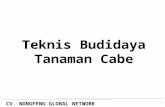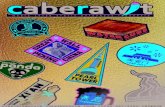Pustaka Cabe
-
Upload
isti-haryanto -
Category
Documents
-
view
338 -
download
0
Transcript of Pustaka Cabe
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Hortikultura atau tanaman sayuran adalah komoditi pertanian yang
memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran. Hal ini disebabkan sayuran dibutuhkan oleh hampir semua orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga tidak heran jika volume peredarannya di pasar dalam skala besar. Kendala usahatani hortikultura di beberapa negara berkembang, adalah rendahnya nilai pendapatan petani, keterbatasan pengetahuan petani, keterbatasan lahan yang dimiliki petani, dan posisi tawar pada pihak petani yang kurang kuat. Hal tersebut menyebabkan rendahnya nilai keuntungan yang diperoleh petani (Ashari, 1995). Menurut Hanani dkk (2003), pemilihan jenis sayuran yang akan diusahakan serta penentuan besarnya skala jenis usaha merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan pengusaha. Jenis sayuran yang dipilih untuk diusahakan adalah sayuran yang memiliki nilai ekonomi atau prospek (peluang) cukup besar dalam pemasaran dan tidak sulit untuk dibudidayakan. Sayuran jenis tersebut biasanya mempunyai banyak peminat. Kalaupun peminatnya tidak banyak, harganya relatif tinggi dan dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor. Cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi cukup besar. Cabai merah merupakan tanaman yang sangat potensial untuk diusahakan. Ini dikarenakan cabai merah sangat banyak dikonsumsi sebagai bumbu penyedap
Universitas Sumatera Utara
rasa pada masakan, bahan campuran industri pengolahan makanan dan minuman, serta digunakan untuk pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Namun biasanya usahatani cabai merah dilakukan dalam skala kecil. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan terhadap harga jual yang selalu berfluktuasi setiap waktu yang akan mempengaruhi hasil usahatani serta pendapatan petani. Dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sering dihadapkan pada permasalahan pengetahuan petani yang masih relatif rendah, keterbatasan modal, lahan garapan yang sempit serta kurangnya keterampilan petani yang nantinya akan berpengaruh pada penerimaan petani. Untuk menghasilkan sayuran segar bermutu tinggi dengan harga dan
keuntungan yang layak, diperlukan penanganan yang baik mulai dari perencanaan tanam hingga pemasarannya ke konsumen (Redaksi Agromedia a, 2008). Sehingga dibutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan cabai merah dari penyemaian bibit hingga pasca panen sehingga petani mendapatkan produksi dan pendapatan yang lebih baik. Dari kendala-kendala usahatani tersebut, sistem pengelolaan sangat mempengaruhi hasil produksi dan pendapatan dari petani. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu dilakukan penelitian mengenai semua jenis sistem pengelolaan serta jumlah pendapatan pada setiap sistem pengelolaan. Tanaman cabai merah paling banyak dijumpai di Kabupaten Karo, dimana kecamatan yang menanamnya antara lain sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1. No
Luas tanam, Luas panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Komoditi Cabai Merah Tahun 2008 Kabupaten Karo. Rata-Rata Kecamatan Luas tanam Luas panen Produksi roduksi (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) 76 115 178 5 199 400 29 41 230 186 188 1.015 498 654 303 154 140 4.411 73 84 28 5 197 250 127 42 165 223 246 265 944 1.124 175 146 79 4.173 852 728 300 26 2.758 750 479 138 1.365 1.333 2.981 1.952 8.944 11.240 850 2.242 734 37.672 11,67 8,67 10,71 5,20 14,00 3,00 3,77 3,29 8,27 5,98 12,12 7,37 9,47 10,00 4,86 15,36 9,29
1 Barus Jahe 2 Berastagi 3 Dolat Rakyat 4 Juhar 5 Kabanjahe 6 Kutabuluh 7 Lau Baleng 8 Mardingding 9 Merdeka 10 Merek 11 Munte 12 Naman Teran 13 Payung 14 Simpang Empat 15 Tiga Binanga 16 Tiga Panah 17 Tiganderget Jumlah
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, Tahun 2009 Dari tabel 1. di atas, terdapat jumlah luas tanam dan luas panen yang berbeda. Ini dikarenakan data yang diambil hanya pada awal tahun hingga akhir tahun. Sehingga jika ada penanaman cabai pada akhir tahun 2008 sedangkan panennya pada awal tahun 2009, maka data luas panen akan masuk data pada tahun 2008 dan luas panen akan masuk pada data pada tahun 2009. Adapun peneliti memilih Kecamatan Kabanjahe sebagai daerah penelitian, dikarenakan Kecamatan Kabanjahe merupakan pusat dari pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Karo. Sehingga dianggap daerah penelitian lebih memiliki kelebihan dari sektor informasi pasar dan kemudahan akses dari sarana produksi pertanian dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2008 produksi cabai di Kecamatan Kabanjahe tercatat luas areal pertanaman cabai hanya mencapai 199 hektar dengan hasil mencapai 2.758 ton atau rata-rata hasil perhektar mencapai 14,00 ton/ha. Hasil tersebut masih rendah karena menurut Pracaya (2000), jika dibudidayakan dengan intensif tanaman cabai bisa mencapai 15 sampai 20 ton/ha. Penyebab rendahnya produksi cabai bisa diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit pada buah cabai, selain itu diduga akibat sistem pengelolaan yang kurang baik. Adapun desa yang dijadikan daerah penelitian adalah Desa Kaban. Ini dikarenakan desa tersebut memiliki luas tanam yang lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. Tabel 2. Luas Tanam Komoditi Cabai Merah Tahun 2010 Kecamatan Kabanjahe No Kelurahan / Desa Luas Tanam Cabai Merah (Ha/Tahun) 1 Gungleto 2 Gunegri 15 3 Kampung Dalam 5 4 Padang Mas 5 Lau Jimba 5 6 Kaban 46 7 Kacaribu 7 8 Kandibata 32 9 Ketaren 10 10 Lau Sinamo 20 11 Rumah Kabanjahe 30 12 Sumber Mufakat (Sumbul) 15 13 Samura 20 Sumber : PPL Kecamatan Kabanjahe 2010
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Identifikasi Masalah
1) Apakah terdapat perbedaan biaya produksi pada setiap jenis pengelolaan cabai merah? 2) Apakah terdapat perbedaan penerimaan pada setiap jenis pengelolaan cabai merah? 3) Apakah terdapat perbedaan pendapatan pada setiap jenis pengelolaan cabai merah? 4) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam pemilihan sistem pengelolaan dengan perlakuan biasa dan perlakuan intensif usahatani cabai merah? 1.3. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengidentifikasikan perbedaan biaya produksi pada setiap jenis pengelolaan tanaman cabai merah. 2) Untuk mengidentifikasikan perbedaan penerimaan pada setiap jenis pengelolaan cabai merah. 3) Untuk mengidentifikasikan perbedaan pendapatan pada setiap jenis pengelolaan cabai merah. 4) Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam pemilihan sistem pengelolaan dengan perlakuan biasa dan perlakuan intensif usahatani cabai merah.
Universitas Sumatera Utara
1.4.
Kegunaan Penelitian
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan pengembangan usahatani cabai merah. 2) Sebagai bahan masukan bagi petani cabai merah untuk meningkatkan produksi cabai merahnya.
Universitas Sumatera Utara
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1.
Tinjauan Pustaka Hingga saat ini, cabai masih tergolong primadona hortikultura. Cabai
merupakan terna tahunan yang tumbuh tegak dengan batang berkayu, banyak cabang, serta ukuran yang mencapai tinggi 120 cm dan lebar tajuk tanaman hingga 90 cm. Umumnya, daun cabai berwarna hijau muda sampai hijau gelap, tergantung varietas. Daun cabai yang ditopang oleh tangkai daun mempunyai tulang menyirip. Daun cabai berbentuk bulat telur, lonjong, ataupun oval dengan ujung yang meruncing, tergantung spesies dan varietasnya. Bunga cabai keluar dari ketiak daun dan berbentuk seperti terompet. Bunga cabai merupakan bunga lengkap yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga cabai juga berkelamin dua, karena benang sari dan putik terdapat dalam satu tangkai. Bentuk buah cabai berbeda-beda, dari cabai keriting, cabai besar yang lurus dan bisa mencapai ukuran sebesar ibu jari, cabai rawit yang kecil-kecil tapi pedas, cabai paprika yang berbentuk seperti buah apel, dan bentuk-bentuk
cabai hias lain yang banyak ragamnya (Redaksi AgroMedia, 2008 b). Dalam pembangunan usahatani kegiatan utama yang harus dilakukan untuk peningkatkan produksi barang pertanian yang dihasilkan petani, meningkatkan produktifitas pertanian serta mendorong perkembangan komoditas yang sesuai dengan potensi wilayah. Peningkatan produksi pertanian apabila ingin meningkatkan pendapatan petani. Kualitas dan kuantitas yang baik dari produk
Universitas Sumatera Utara
pertanian yang dihasilkan petani sangat mempengaruhi pendapatan petani (Hanani, Jabal, dan Mangku. 2003) Untuk menutup keran impor cabai perlu diupayakan usaha perluasan
lahan penanaman serta inovasi baru dalam teknologi budidaya cabai. Salah satu cara yang memungkinkan adalah dengan terobosan teknologi budidaya cabai yang mampu menghasilkan produksi tinggi pada luasan lahan yang terbatas. Teknologi tersebut berupa penggunaan benih hibrida, mulsa, pemeliharaan secara intensif, serta ditunjang oleh pengelolaan yang profesional (Prajnanta, 1999).
2.2
Landasan Teori
2.2.1. Jenis pengelolaan Dalam sebuah usahatani, faktor produksi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut Mubyarto (1991), faktor produksi terdiri dari empat komponen, yaitu tanah atau lahan, modal, tenaga kerja dan skill atau manajemen pengelolaan. Keberadaan dari sistem pengelolaan tidak akan menyebabkan proses produksi tidak berjalan atau batal. Namun pengelolaan hanya menekankan pada usahatani yang maju dan berorientasi pasar (keuntungan). Kemampuan pengelolaan sangat penting, karena usahatani bukanlah semata-mata hanya sebagai cara hidup. Jatuh-bangunnya suatu usaha salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola faktor-faktor produksi (Rahardi dkk, 2007). Menurut Tohir dalam Suratiyah (2009), dalam usahatani sering ditemukan istilah intensif dan ekstensif (perlakuan biasa) yang tidak mudah untuk menentukan perbedaannya karena tidak memiliki sifat yang mutlak. Usahatani
Universitas Sumatera Utara
dikatakan intensif jika banyak menggunakan tenaga kerja dan atau modal per satuan luas, dan sebaliknya. Pertanian intensif dan ekstensif berkonotasi terhadap jumlah input perhektar, seperti penggunaan teknologi dan penggunaan mesin atau tenaga manual. Intensif dan ekstensif berlaku antara waktu, antar daerah dan antar tanaman/usaha. Indikatornya adalah jumlah pengunaan input persatuan luas (Tarigan, 2001). Menurut PPL (penyuluh pertanian lapangan) Kecamatan Kabanjahe, sistem pengelolaan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dari perlakuan biasa hingga perlakuan yang sangat intenif. Namun untuk tanaman cabai merah hanya dibagi atas dua perlakuan, yaitu perlakuan intensif dan perlakuan biasa (tradisional/ekstensif). Istilah intensifikasi banyak sekali digunakan di negara kita dan menjadi sangat populer terutama dalam hubungan usaha peningkatan produksi. Intensifikasi dimaksudkan penggunaan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja dan modal atas sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar. Dengan program intensifikasi, yaitu dengan penggunaan bibit unggul yang akan meningkatkan hasil produksi. Program intensifikasi besar-besaran dalam produksi juga ditempuh melalui sarana produksi (seperti : pupuk, obat-obatan, pemberantasan hama dan penyakit, kredit dan air irigasi) yang digunakan secara efektif dan efisien (Mubyarto, 1991). Dalam sistem pertanian yang pada umumnya dapat digolongkan dalam tingkat pengelolaan yang kurang intensif, maka kualitas dan kuantitas hasil produksinya juga tidak maksimal. Hal ini disebabkan produksi sangat dipengaruhi
Universitas Sumatera Utara
input yang digunakan dan keterampilan dari petani. Dan biasanya pengelolaan dengan perlakuan biasa dilakukan oleh petani hanya sebagai sambilan atau untuk konsumsi sendiri. Penanaman tanaman hortikultura dalam stadium primitif tidak
memerlukan perhahatian khusus, seperti jarak tanam, pemupukan atau pemberantasan hama dan penyakit. Dengan demikian modal usahatani juga masih relatif rendah, sehingga produk yang dipasarkan pun tidak memberikan keuntungan yang besar (Ashari, 1995). Menurut Barus dan Syukri (2008), pertanian tradisional (perlakuan biasa) memiliki ciri antra lain : 1) Kultivar lokal dan umumnya dari bibit sembarangan. 2) Jarak tanam kurang diperhatikan. 3) Lokasi sering kurang sesuai dengan agroklimat varietas yang ditanam. 4) Perawatan belum memadai seperti: pemupukan, pemangkasan, dan sebagainya.
2.2.2. `Pendapatan Usahatani hortikultura memerlukan biaya dan tenaga kerja terampil serta sarana yang lebih mahal dibandingkan dengan usahatani tanaman pangan. Tanaman hortikultura perlu lebih intensif, sehingga memerlukan modal yang lebih besar. Namun dengan demikian, nilai jual tanaman hortikultura pun lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan yang lebih memadai (Ashari, 1995). Petani selalu dihadapkan dengan masalah pengambilan keputusan tentang bagaimana petani harus mengoperasikan usahataninya, sehingga diperoleh hasil dan kepuasan maksimal. Umumnya sebelum mengambil keputusan untuk
Universitas Sumatera Utara
menanam suatu komoditi, petani memperhitungkan penerimaan dan biaya produksi. Sehingga pada akhirnya akan diketahui pendapatan yang akan diterima oleh petani. Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang bersifat reguler yang diterima sebagai balas jasa. Sedangkan pendapatan petani adalah total penerimaan yang diperoleh petani dari usahatani yang diusahakannya dikurangi dengan total pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan. Jumlah pendapatan yang besar menunujukkan besarnya modal yang dimiliki petani untuk mengelola usahataninya sedangkan jumlah pendapatan yang kecil menunjukkan investasi yang menurun sehingga berdampak buruk terhadap usahataninya
(Soekartawi, 1995). Biaya produksi sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh petani, baik bersumber dari modal sendiri maupun dari luar. Menurut Soekartawi (2003), biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. Biaya produksi yang digunakan terdiri dari sewa tanah, bunga modal, biaya sarana produksi untuk bibit, pupuk dan obat-obatan serta sejumlah tenaga kerja. Dalam pertanian yang ada di lapangan, biaya yang dianggap ada oleh petani hanya meliputi biaya yang dikeluarkan secara nyata. Sedangkan biaya yang dimiliki oleh petani sajak lama, tidak dimasukkan kedalam pembiayaan usahatani. Menurut Sukirno (2005), biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis : biaya eksplesit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplesit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran
Universitas Sumatera Utara
dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Biaya dapat dibedakan menjadi biaya tetap (FC = Fixed Cost) dan biaya variabel (VC = Variable Cost). Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi, misalnya biaya sewa/pajak lahan, dan biaya penyusutan. Dan biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi, misalnya sarana produksi, dan tenaga kerja luar keluarga (Suratiyah, 2009). Penerimaan petani adalah akumulasi dari perkalian dari produksi yang dihasilkan petani dengan harga jual cabai merah pada saat pemanenan. Pemanenan biasanya dilakukan satu hingga dua hari dalam seminggu, dan dapat dilakukan kira-kira selama enam bulan masa panen. Sedangkan harganya sangat berfruktuasi dengan keadaan pasar.
2.2.3. Uji beda Uji-t dua sampel independen (Independen Sampel t-Test) digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (mean) dari dua sampel yang idenpenden dengan asumsi data terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2005), untuk melakukan uji beda terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut ini memberikan pedoman penggunaannya : 1) Bila jumlah sampel n1 = n2, dan varians homogen (12 = 22) maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk Separated maupun Pooled varians. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 2.
Universitas Sumatera Utara
2) Bila n1 n2, varians homogen (12 = 22), dapat digunakan dengan Pooled varians. Derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 2. 3) Bila n1 = n2, varians tidak homogen (12 22), dapat digunakan dengan Separated dan Pooled varians. Dengan dk = n1 1 atau n2 1. jadi dk bukan + n2 2. 4) Bila n1 n2 dan varians tidak homogen (12 22). Untuk ini digunakan ttest dengan Separated varians. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1 1) dan dk (n2 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil.t-hitung = x1 - x2 S1 2 S2 2 + n1 n1
...................................... Separated varians.
t-hitung =
x1 - x2 (n1 - 1)S 1 2 + (n2 - 1)S 2 2 1 1 + n1 + n 2 n1 n 2x1 - x2 S1 2 S2 2 + - 2r n1 n2 S1 n1 S2 n2
.. Pooled varians.
t-hitung =
......... sampel berpasangan/related.
Keterangan :x1 =Rata-rata nilai variabel I x 2 =Rata-rata nilai variabel II
S1=Rata-rata standar deviasi variabel I S2=Rata-rata standar deviasi variabel I n1=Jumlah sampel variabel I n2=Jumlah sampel variabel II
Universitas Sumatera Utara
2.2.4. Regresi Logistik Regresi logistik lebih dikenal dengan regresi logit, digunakan saat variabel respon (terikat) memiliki dua variabel (misalnya binari atau 0 1). Variabel prediktor mungkin jumlah, kategori atau campuran keduanya. Regresi dua variabel umumnya banyak digunakan pada situasi ini. Ketika ini terjadi, model ini disebut model probabilitas linier (Rusdin, 2004). Menurut Chairullah (2004), Regresi logistik dirancang untuk melakukan prediksi keanggotaan group. Artinya tujuan dari analisis regresi logistik adalah untuk mengetahui seberapa jauh model yang digunakan mampu memprediksi secara benar kategori group dari sejumlah individu.
Syarat-syarat regresi logistik : 1) Variabel independent merupakan campuran antara variabel diskrit dan kontinyu; 2) Distribusi data yang digunakan tidak normal.
Kelebihan regresi logistik disbanding regresi yang lain : 1) Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya variabel penjelas tidak harus memiliki distribusi normal, linier, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap group. 2) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinyu, diskrit dan dikotomis; 3) Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan non linier dengan satu atau lebih variabel bebas.
Universitas Sumatera Utara
Karena model yang dihasilkan dengan regresi logistik bersifat non linier, persamaan yang digunakan untuk mendiskripsikan hasil sedikit lebih komplek di banding regresi berganda. Variabel hasil Y adalah probabilitas mendapatkan 2 hasil atau lebih berdasarkan fungsi non linier dari kombinasi linier sejumlah variabel bebas. Menurut Hosmer and Lemeshow dalam Handayani (2005) Regresi logistic bertatar (stepwise logistic regression) digunakan untuk menentukan peubahpeubah penjelas yang bisa membedakan respon yang diamati. Prosedur ini memilih atau menghilangkan peubah-peubah satu persatu dari model sampai ditemukan peubah-peubah yang berpengaruh nyata terhadap model.
2.3.
Kerangka Pemikiran Proses produksi usahatani dilihat dari sistem pengolahannya dapat dibagi
menjadi dua, yaitu perlakuan biasa dan perlakuan intensif. Pada kedua perlakuan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yaitu lahan, modal dan tenaga kerja. Petani dalam hal ini memilih diantara kedua perlakuan tersebut. Adapun faktor-faktor pemilihan sistem pengelolaan, yaitu : tenaga kerja dalam keluarga, tingkat pendidikan, dan pengalaman bertani cabai merah. Dari kedua perlakuan ini, faktor produksi akan mengakibatkan biaya produksi yang berbeda sesuai dengan perlakuan yang dipilih petani. Perlakuan ini akan menghasilkan jumlah produksi yang berbeda. Cabai yang diproduksi akan dijual. Penjualan cabai akan memberikan penerimaan bagi petani. Dengan membandingkan antara penerimaan dan biaya produksi yang dikeluarkan akan diperoleh pendapatan bersih petani antara mengunakan
Universitas Sumatera Utara
perlakuan biasa dan perlakuan intensif. Secara umum dapat digambarkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut :
Kerangka Pemikiran
Usaha Tani Cabai
Sistem Pengelolaan Faktor Produksi - Lahan - Modal - Tenaga Kerja
Perlakuan Biasa
Perlakuan Intensif Faktor pemilihan sistem pengelolaan - Tenaga kerja dalam keluarga - Pendidikan - Pengalaman
Jumlah Produksi Biaya Produksi Penerimaan Harga jual
Pendapatan Bersih Keterangan : = Menyatakan adanya hubungan = Menyatakan mempengaruhi Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Uji Beda Pendapatan Pada Berbagai Pengelolaan Cabai Merah.
Universitas Sumatera Utara
2.4.
Hipotesis Penelitian Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dirumuskan
hipotesis penelitian sebagai berikut : 1) Perbedaan pengelolaan usahatani memberikan pengaruh yang nyata terhadap biaya produksi. 2) Perbedaan pengelolaan usahatani memberikan pengaruh yang nyata terhadap penerimaan. 3) Perbedaan pengelolaan usahatani memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR PUSTAKA
Ashari, S., 1995. Hortikultura : Aspek Budidaya. UI press, Jakarta. Barus, A. dan Syukri, 2008. Agroekoteknologi Tanaman Buah-buahan. USU Press, Medan. Chairullah, A. W., 2004. Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas di Lingkup Pertanian Kabupaten Sampang (Tinjauan berdasarkan Metode Analisis Fungsi Statistik). http://www.damandiri.co.id/ April 2010. Ghozali, I., 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisis Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Hanani, N.A.R., J.T. Ibrahim dan M. Purnomo, 2003. Strategi Pembangunan Pertanian : Sebuah Pemikiran Baru. LAPPERA PUSTAKA UTAMA, Yogyakarta. Handayani, M.W., 2005. Analisis Regresi Logistik. http://repository.ipb.ac.id Februari 2011 Harpanes, A. dan Dermawan, S., 2011. Budidaya Cabai Unggul. Penebar Swadaya, Jakarta. Nachrowi, N.D., dan H. Usman. 2008. Penggunaan Teknik Ekonometrika. Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Mubyarto, 1991. Pengantar Ilmu Pertanian. Edisi ke-3, Cetakan ke-2. LP3ES, Jakarta. Rahardi, F., Indriani Y.H., Haryanto, dan Aji ER., 2007. Agribisnis : Tanaman Buah. Edisi revisi. Penebar Swadaya, Jakarta. Pracaya. 2000. Bertanam Lombok. Kanisus Yogyakarta. Prajnanta, F., 1999. Agribisnis Cabai Hibrida. Cetakan ke-7. Penebar Swadaya. Jakarta. Redaksi AgroMedia, 2008 a. Budi Daya Cabaimerah pada Musim Hujan. Cetakan ke-3. Agromedia Pustaka. Jakarta. ________________, 2008 b. Panduan Lengkap Agrobisnis Budi Daya dan Bisnis Cabai. Cetakan ke-1. Agromedia Pustaka, Jakarta. Rusdin, 2004. Statistika : Peneitian Sebab Akibat. Pustaka Bani Quraisy, Bandung. Sevilla, C.G., 1993. Pengantar Metode Penelitian. UI Press, Jakarta. Soekartawi, 1995. Analisis Usahatani. UI press. Jakarta. _________, 2003. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Universitas Sumatera Utara
Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-8. Alfabeta, Bandung. Sukirno, S., 2005. Mikro Ekonomi Teori Pengeantar. Grafindo Husada, Jakarta. Suratiyah, K., 2009. Ilmu Usahatani. Cetakan ke-3. Penebar Swadaya. Jakarta. Tarigan, K., 2001. Pengantar Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian, USU, Medan.
Universitas Sumatera Utara